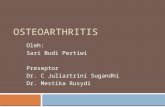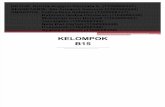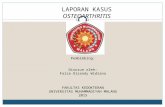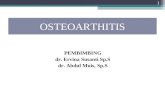OA
-
Upload
eka-ustavia-widyastuti -
Category
Documents
-
view
37 -
download
13
description
Transcript of OA
PORTOFOLIO
I. Identitas PasienNama Pasien: Ny. RUmur: 75 tahunJenis Kelamin: PerempuanAlamat:DemakPekerjaan: Ibu Rumah TanggaStatus Perkawinan: MenikahAgama: IslamSuku: JawaNo. Rekam Medik: 026165Tanggal Periksa RS: 6 januari 2015
II. AnamnesisRiwayat keluhan pasien diperoleh secara autoanamnesis dan alloanamnesis (anak pasien) yang dilakukan pada tanggal : 6 januari 2015.1. Keluhan UtamaKedua lutut nyeri 2. Riwayat Penyakit SekarangPasien datang diantar keluarganya dengan keluhan kedua lutut terasa nyeri dan sulit untuk berjalan. Keluhan ini dirasakan pasien secara tiba tiba sejak 4 hari sebelum periksa. Nyeri dirasakan pasien seperti berdenyut dan tertusuk jarum. Nyeri tersebut juga tidak menghilang dengan kompres, minyak urut, maupun obat pengurang rasa sakit. Nyeri semakin memberat saat pasien melipat lututnya dan menggerakkan kakinya tetapi sedikit berkurang dengan istirahat. Awalnya, pasien mengaku mendapatkan keluhan nyeri dan sulit berjalan ini ketika pasien ingin beranjak dari tempat tidurnya menuju kamar mandi. Ketika akan berdiri, pasien merasakan kedua kakinya sangat nyeri dan sulit untuk digerakkan hingga pasien terjatuh ke lantai. Pasien menyangkal adanya benturan di kepala saat jatuh. Riwayat pingsan setelah jatuh, mual, muntah, sesak, kejang, pusing, lumpuh separo, cedal, pelo, merot semuanya juga disangkal. Riwayat makan minum, buang air besar dan buang air kecil semuanya masih dalam batas normal. Sebenarnya, pasien sudah lama merasakan nyeri pada kedua lututnya ini yaitu selama 1 tahun SMRS, namun perlahan dirasa semakin memberat sejak ada bengkak di kedua lututnya dan puncaknya yaitu 4 hari sebelum periksa karena keluhan pasien ini menyebabkan dirinya tidak bisa berjalan lagi. Pasien mengaku baru menyadari ada pembengkakan di kedua lututnya ini kira kira 6 bulan terakhir. Bengkak tersebut menyebabkan pasien susah menggerakkan kakinya dan menyebabkan terhambatnya aktivitas sehari hari pasien. Namun, pasien masih bisa berjalan pelan pelan tanpa tongkat. Di daerah lutut yang bengkak tersebut terasa hangat. Pasien mengatakan bengkaknya tidak mengecil setelah dikompres dengan air dingin ataupun setelah pasien beristirahat.
Selain keluhan nyeri dan bengkak, pasien juga merasakan kaku pada kedua lututnya. Biasanya kaku ini muncul pada pagi hari setelah pasien bangun tidur dan menetap sekitar setengah jam. Saat kaku ini muncul, pasien tidak bisa menggerakkan kakinya sama sekali, pasien hanya bisa diam di tempat tidur. kadang pasien juga merasakan gemertak ketika lututnya digerakkan. Pasien mengaku sudah pernah berobat ke dokter penyakit dalam dan di cek laboratorium dan di foto rongen di bagian kaki 1 bulan yang lalusudah di beri terapi tetapi keluhan tidak membaik. Pasien di suruh control tetapi tidak kontrol. Pasien juga mengaku bahwa sebelum sakit selama 1 tahun ini, pasien masih sering melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu dan memasak, tetapi semenjak kedua lututnya terasa nyeri pasien hanya bisa berjalan santai di sekeliling rumahnya.
3. Riwayat Penyakit Dahulua. Riwayat Keluhan Serupa: diakui (sudah 1 tahun, tetapi pasien masih bisa berjalan) b. Riwayat Kencing Manis: disangkalc. Riwayat Darah Tinggi: diakui (sudah > 2 tahun tetapi tidak rutin konsumsi OAH)d. Riwayat Penyakit Jantung : disangkale. Riwayat Sakit Ginjal: disangkalf. Alergi Obat dan Makanan : disangkalg. Riwayat Asma : disangkalh. Riwayat Sakit Maag: disangkali. Riwayat Operasi : disangkalj. Riwayat Opname di RS: disangkalk. Riwayat Asam Urat: pernah di cek normall. Riwayat Kolesterol: pernah di cek normalm. Riwayat Trauma / Jatuh: disangkal4. Riwayat Penyakit Keluargaa. Riwayat Penyakit Serupa: disangkalb. Riwayat Darah Tinggi: disangkalc. Riwayat Kencing Manis : disangkald. Riwayat Penyakit Jantung : disangkale. Riwayat Penyakit Ginjal: disangkalf. Riwayat Asma : disangkal5. Riwayat Kebiasaana. Riwayat Minum Jamu dan Obat Bebas: disangkalb. Riwayat Minum Alkhohol: disangkalc. Riwayat Merokok: disangkald. Riwayat Minum Suplemen: disangkale. Riwayat Makan Makanan Berlemak: disangkal6. Riwayat Lingkungan dan SosialPasien adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di dalam lingkungan tempat tinggal yang cukup bersih bersama anaknya. Pasien menggunakan fasilitas BPJS NON PBI untuk biaya pengobatan.III. PEMERIKSAAN FISIKPemeriksaan fisik dilakukan pada tanggal 6 Januari 2015 di poliklinik syaraf.1. Keadaan umum: sedang, tampak kesakitan2. Kesadaran: composmentis, GCS : E4V5M6 : 153. Tanda Vitala. Tekanan darah: 160/110 mmHg, posisi berbaring, lengan kirib. Nadi: 86 x/menit, reguler, kuat, isi dan tegangan cukupc. Respirasi: 18x/menit, tipe thorakoabdominald. Suhu: 37C, per axiler4. Status GiziBB = 65 kgTB = 155 cmBMI= 65= 27,05 kg/m2 (harga normal = 18,5-22,5 kg/m2) (1,55)2 Kesan : overweight 5. Pemeriksaan fisika. KepalaBentuk mesocephal, rambut warna hitam, sebagian beruban, mudah rontok (-), tidak mudah dicabut (+), luka (-)1) WajahSimetris, eritema (-), ruam muka (-), luka (-).2) MataKonjungtiva palpebra anemis (-/-), sklera ikterik (-/-), oedem palpebra (-/-), sianosis (-), pupil isokor (3mm/ 3mm), reflek cahaya direct/indirect (+/+), perdarahan subkonjungtiva (-/-)3) TelingaSekret (-), darah (-), nyeri tekan mastoid (-) gangguan fungsi pendengaran (-)4) HidungDeviasi septum nasi (-), epistaksis (-), nafas cuping hidung (-), sekret (-), fungsi pembau baik, foetor ex nasal (-)5) MulutSianosis (-), gusi berdarah (-), kering (-), stomatitis (-), pucat(-) lidah tifoid (-), papil lidah atropi (-), luka pada sudut bibir (-)b. LeherLeher simetris, retraksi suprasternal (-), deviasi trachea (-), JVP R0, pembesaran kelenjar limfe (-), pembesaran kelenjar tiroid (-).c. ThoraxBentuk normochest, simetris, retraksi intercostalis (-), pernafasan thorakoabdominal, sela iga melebar (-), jejas (-).Jantung 1) Inspeksi : Iktus kordis tidak tampak2) Palpasi : Iktus kordis tidak kuat angkat
3) Perkusi : Batas jantungKiri atas: SIC II linea parasternalis sinistraKiri bawah: SIC V 2 cm medial linea midclavicularis sinistraKanan atas: SIC II linea parasternalis dextraKanan bawah: SIC IV linea parasternalis dextraPinggang jantung: SIC II-III parasternalis sinistra Konfigurasi jantung kesan tidak melebar4) Auskultasi: Bunyi jantung I-II murni, intensitas, reguler, bising (-), gallop (-).Paru - Paru1) InspeksiNormochest, sela iga tidak melebar, gerakan pernafasan simetris kanan kiri, retraksi intercostae (-).2) PalpasiKetinggalan gerakDepanBelakang----
----
----
FremitusDepan BelakangNNNN
NNNN
NNNN
3) Perkusi:DepanBelakangSonorSonorSonorSonor
SonorSonorSonorSonor
SonorSonorSonorSonor
4) Auskultasi:Suara dasar vesikulerDepanBelakang++++
++++
++++
Suara tambahan : wheezing (-/-), ronkhi (-/-)d. Abdomen1) InspeksiDinding perut sejajar dinding dada, distended (-), umbilikus tampak dan tidak ada inflamasi, kaput medusa (-), venektasi (-), sikatrik bekas operasi (-).2) Auskultasi Peristaltik (+) normal.3) PerkusiTimpani (+), ascites (-), shifting dullnes (-)4) PalpasiSupel, nyeri tekan epigastrium (-), lien dan hepar tidak teraba membesar, ginjal tidak teraba, nyeri ketok costovertebrae (-), defans muskular (-)
e. Ekstremitas1) Ekstremitas superior DekstraPergerakan motorik dalam batas normal, tanda-tanda inflamasi (-), oedem (-), eritem (-), CRT < 3 detik, clubbing finger (-), kuku nekrosis (-), akral hangat (+), deformitas (-).SinistraPergerakan motorik dalam batas normal, tanda-tanda inflamasi (-), oedem (-), eritem (-), CRT < 3 detik, clubbing finger (-), kuku nekrosis (-), akral hangat (+), deformitas (-).2) Ekstremitas inferiorDekstraPergerakan motorik sendi lutut terbatas (+), tanda-tanda inflamasi sendi lutut (+), oedem sendi lutut (+), deformitas sendi lutut (+), krepitasi sendi lutut (+), nyeri gerak dan tekan (+), hiperemi (-), kuku nekrosis (-), akral hangat (+).SinistraPergerakan motorik sendi lutut terbatas (+), tanda-tanda inflamasi sendi lutut (+), oedem sendi lutut (+), deformitas sendi lutut (+), krepitasi sendi lutut (+), nyeri gerak dan tekan(+), hiperemi (-), kuku nekrosis (-), akral hangat (+).
IV. PEMERIKSAAN PENUNJANG1. Laboratorium Darah dan Urin (tanggal 9 Desember 2014)Keterangan9/12/2014SatuanNilai Rujukan
Hematologi rutin
Hemoglobin11,8g/dl11,5-16
Hematokrit36,9%35-49
Leukosit8,310/l4,0-11
Trombosit29710/l150-440
Eritrosit5,0510/l3,8-5,2
Indeks eritrosit
MCV73,1fl82-95
MCH23,3pg27-31
MCHC31,9g/dl32-36
RDW18,5%11,6-14,8
Hitung jenis
Granulosit73,2 %50-70
Limfosit17,0%20-40
Monosit9,8 %2-8
Kimia Ginjal
Ureum16mg/dL10-45
Creatinin0,73mg/dL0,5-1,1
Asam Urat6.0mg/dL2,4-6.0
GDS199mg/dL< 200
Kimia Profil Lipid
Kolesterol Total199mg/dL40
LDL Kolesterol134,8 mg/dL< 130
Trigliserid146mg/dL35-160
2. Foto Rontgen (tanggal 9 Desember 2014)X Ray Genu Dekstra et Sinistra
Kesan : Osteofit pada condylus lateralis dan medialis os tibia femoralis dekstra disertai penyempitan sendi tibia femoralis lateralis dekstra merupakan gambaran osteoarthrosis genu dekstra grade III. Osteofit pada condylus lateralis dan medialis os tibia femoralis sinistra disertai penyempitan sendi femoro tibialis sinistra disertai irreguler pada tulang tibia fibula sekitar sendi dan sklerotik subcondral merupakan gambaran osteoarthosis genu sinistra grade IV disertai osteoarthritis / peradangan.
V. DIAGNOSISOsteoartritis Genu Dextra et SinistraHipertensi grade II
VI. PENATALAKSANAAN1. FarmakoterapiMeloxicam 15 mg 1x1Ranitidin 2x1 tab a.cDiazepam 2 mg 2x1Neurodex 2x1Glucosamin 500 mg 1x1Amlodipine 10 mg 1x12. NonfarmakologiFisioterapi IR, TENS genue dextra et sinistra, strengthening exercisePenurunan berat badanDiit rendah garam
VII. PROGNOSISQua ad vitam : Dubia ad bonamQua ad functionam : Dubia ad malamQua ad sanationam : Dubia ad malam
TINJAUAN PUSTAKAOSTEOARTHRITISI. Definisi Osteoarthritis (OA, dikenal juga sebagaiarthritis degeneratif,penyakit degeneratif sendi) merupakan penyakit sendi degeneratif yang mengenai sendi-sendi penumpu berat badan dengan gambaran patologis yang berupa kerusakan kartilago sendi, dimana terjadi proses degradasi interaktif sendi yang kompleks, terdiri dari proses perbaikan pada kartilago, tulang dan sinovium diikuti komponen sekunder proses inflamasi.1,2
II. EpidemiologiOsteoartritis merupakan penyakit sendi yang paling banyak ditemukan di dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan sejak tahun 2001 hingga 2010 dicanangkan sebagai dekade penyakit tulang dan sendi di seluruh dunia.5 Penyakit ini menempati urutan kedua setelah penyakit kardiovaskuler sebagai penyebab ketidakmampuan fisik. Di Inggris dan Wales, sekitar 1,3 hingga 1,75 juta orang mengalami gejala OA. Di Amerika, 1 dari 7 penduduk menderita OA.3,4 Di Australia pada tahun 2002, diperkirakan biaya nasional untuk OA sebesar 1% dari GNP, yaitu mencapai $Aus 2.700/orang/tahun.4 Di Indonesia sendiri, prevalensi total OA sebanyak 34,3 juta orang pada tahun 2002 dan mencapai 36,5 juta orang pada tahun 2007. Diperkirakan 1 sampai 2 juta orang lanjut usia di Indonesia menderita cacat karena osteoarthritis. Pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan terjadinya osteoarthritis pada obesitas dan sendi penahan beban tubuh.5 Dari sekian banyak sendi yang dapat terserang OA, lutut merupakan sendi yang paling sering dijumpai terserang OA. Data Arthritis Research Campaign menunjukkan bahwa lebih dari 550 ribu orang di Inggris menderita OA lutut yang parah dan lebih dari 80 ribu operasi replacement sendi lutut dilakukan di Inggris pada tahun 2000 dengan biaya 405 juta Poundsterling.6
III. Patofisiologi OsteoartritisTerjadinya OA tidak lepas dari banyak persendian yang ada di dalam tubuh manusia. Sebanyak 230 sendi menghubungkan 206 tulang yang memungkinkan terjadinya gesekan. Untuk melindungi tulang dari gesekan, di dalam tubuh ada tulang rawan. Namun karena berbagai faktor risiko yang ada, maka terjadi erosi pada tulang rawan dan berkurangnya cairan pada sendi. Tulang rawan sendiri berfungsi untuk meredam getar antar tulang. Tulang rawan terdiri atas jaringan lunak kolagen yang berfungsi untuk menguatkan sendi, proteoglikan yang membuat jaringan tersebut elastis dan air (70% bagian) yang menjadi bantalan, pelumas dan pemberi nutrisi.9,10Kondrosit adalah sel yang tugasnya membentuk proteoglikan dan kolagen pada rawan sendi. Osteoartritis terjadi akibat kondrosit gagal mensintesis matriks yang berkualitas dan memelihara keseimbangan antara degradasi dan sintesis matriks ekstraseluler, termasuk produksi kolagen tipe I, III, VI dan X yang berlebihan dan sintesis proteoglikan yang pendek. Hal tersebut menyebabkan terjadi perubahan pada diameter dan orientasi dari serat kolagen yang mengubah biomekanik dari tulang rawan, sehingga tulang rawan sendi kehilangan sifat kompresibilitasnya yang unik.9Selain kondrosit, sinoviosit juga berperan pada patogenesis OA, terutama setelah terjadi sinovitis, yang menyebabkan nyeri dan perasaan tidak nyaman. Sinoviosit yang mengalami peradangan akan menghasilkan Matrix Metalloproteinases (MMPs) dan berbagai sitokin yang akan dilepaskan ke dalam rongga sendi dan merusak matriks rawan sendi serta mengaktifkan kondrosit. Pada akhirnya tulang subkondral juga akan ikut berperan, dimana osteoblas akan terangsang dan menghasilkan enzim proteolitik. 9,10Agrekanase merupakan enzim yang akan memecah proteoglikan di dalam matriks rawan sendi yang disebut agrekan. Ada dua tipe agrekanase yaitu agrekanase 1 (ADAMTs-4) dan agrekanase 2 (ADAMTs-11). MMPs diproduksi oleh kondrosit, kemudian diaktifkan melalui kaskade yang melibatkan proteinase serin (aktivator plasminogen, plamsinogen, plasmin), radikal bebas dan beberapa MMPs tipe membran. Kaskade enzimatik ini dikontrol oleh berbagai inhibitor, termasuk TIMPs dan inhibitor aktifator plasminogen. Enzim lain yang turut berperan merusak kolagen tipe II dan proteoglikan adalah katepsin, yang bekerja pada pH rendah, termasuk proteinase aspartat (katepsin D) dan proteinase sistein (katepsin B, H, K, L dan S) yang disimpam di dalam lisosom kondrosit. Hialuronidase tidak terdapat di dalam rawan sendi, tetapi glikosidase lain turut berperan merusak proteoglikan.10Berbagai sitokin turut berperan merangsang kondrosit dalam menghasilkan enzim perusak rawan sendi. Sitokin-sitokin pro-inflamasi akan melekat pada reseptor di permukaan kondrosit dan sinoviosit dan menyebabkan transkripsi gene MMP sehingga produksi enzim tersebut meningkat. Sitokin yang terpenting adalah IL-1, selain sebagai sitokin pengatur (IL-6, IL-8, LIFI) dan sitokin inhibitor (IL-4, IL-10, IL-13 dan IFN-). Sitokin inhibitor ini bersama IL-Ira dapat menghambat sekresi berbagai MMPs dan meningkatkan sekresi TIMPs. Selain itu, IL-4 dan IL-13 juga dapat melawan efek metabolik IL-1. IL-1 juga berperan menurunkan sintesis kolagen tipe II dan IX dan meningkatkan sintesis kolagen tipe I dan III, sehingga menghasilkan matriks rawan sendi yang berkualitas buruk. 9,10
IV. Klasifikasi OsteoartritisOA dapat terjadi secara primer (idiopatik) maupun sekunder, seperti yang tercantum di bawah ini :19IDIOPATIKSEKUNDER
SetempatTangan- nodusHeberdendanBouchard(nodal)- artritis erosif interfalang- karpal-metakarpal IKaki: - haluks valgus- haluks rigidus- jari kontraktur (hammer/cock-up toes)- talonavikulareCoxae- eksentrik (superior)- konsentrik (aksial, medial)- difus (koksa senilis)Vertebra- sendi apofiseal- sendi intervertebral- spondilosis (osteofit)- ligamentum (hiperostosis, penyakitForestier, diffuse idiopathic skeletal hyperostosis=DISH)Tempat lainnya:- glenohumeral- akromioklavikular- tibiotalar- sakroiliaka- temporomandibularMenyeluruh:Meliputi 3 atau lebih daerah yang tersebut diatas (Kellgren-Moore)
Trauma akut kronik (okupasional, port)Kongenital atau developmental:Gangguan setempat: PenyakitLeg-Calve-Perthes Dislokasi koksa kongenital Slipped epiphysisFaktor mekanik Panjang tungkai tidak sama Deformitas valgus / varus Sindroma hipermobilitasMetabolik Okronosis (alkaptonuria) Hemokromatosis PenyakitWilson PenyakitGaucherEndokrin Akromegali Hiperparatiroidisme Diabetes melitus Obesitas HipotiroidismePenyakit Deposit Kalsium Deposit kalsium pirofosfat dihidrat Artropati hidroksiapatitPenyakit Tulang dan Sendi lainnya Setempat: FrakturNekrosis avaskular
Tabel 2.1 Osteoartritis Idiopatik dan Sekunder
V. Manifestasi Klinis 151. Nyeri sendiTerutama bila sendi bergerak atau menanggung beban, yang akan berkurang bila penderita beristirahat.2. Kaku pada pagi hari (morning stiffness)Kekakuan pada sendi yang terserang terjadi setelah imobilisasi yang cukup lama (gel phenomenon), bahkan sering disebutkan kaku muncul pada pagi hari setelah bangun tidur (morning stiffness).3. Hambatan pergerakan sendiHambatan pergerakan sendi ini bersifat progresif lambat, bertambah berat secara perlahan sejalan dengan bertambahnya nyeri pada sendi.4. KrepitasiRasa gemeretak (seringkali sampai terdengar) yang terjadi pada sendi yang sakit.5. Perubahan bentuk sendiSendi yang mengalami osteoarthritis biasanya mengalami perubahan berupa perubahan bentuk dan penyempitan pada celah sendi.6. Perubahan gaya berjalanHal yang paling meresahkan pasien adalah perubahan gaya berjalan, hampir semua pasien osteoarthritis pada pergelangan kaki, lutut dan panggul mengalami perubahan gaya berjalan (pincang).
VI. Faktor Risiko Osteoartritis Lutut (Genu)Secara garis besar, terdapat dua pembagian faktor risiko OA lutut yaitu faktor predisposisi dan faktor biomekanis.1. Faktor Predisposisia. Faktor Demografi1) UmurDari semua faktor risiko untuk timbulnya osteoartritis, faktor ketuaan adalah yang terkuat. Proses penuaan dianggap sebagai penyebab peningkatan kelemahan di sekitar sendi, penurunan kelenturan sendi, kalsifikasi tulang rawan dan menurunkan fungsi kondrosit, yang semuanya mendukung terjadinya OA. Studi Framingham menunjukkan bahwa 27% orang berusia 63 70 tahun memiliki bukti radiografik menderita OA lutut, yang meningkat mencapai 40% pada usia 80 tahun atau lebih.7 2) Jenis kelaminPrevalensi OA pada laki-laki sebelum usia 50 tahun lebih tinggi dibandingkan perempuan, tetapi setelah usia lebih dari 50 tahun prevalensi perempuan lebih tinggi menderita OA dibandingkan laki-laki. Hal ini dikaitkan dengan pengurangan hormon estrogen yang signifikan pada wanita.8 3) Ras / EtnisPrevalensi OA lutut pada penderita di negara Eropa dan Amerika tidak berbeda, sedangkan suatu penelitian membuktikan bahwa ras Afrika Amerika memiliki risiko menderita OA lutut 2 kali lebih besar dibandingkan ras Kaukasia. Penduduk Asia juga memiliki risiko menderita OA lutut lebih tinggi dibandingkan Kaukasia.10,11 Suatu studi lain menyimpulkan bahwa populasi kulit berwarna lebih banyak terserang OA dibandingkan kulit putih.9b. Faktor GenetikFaktor herediter juga berperan pada timbulnya osteoartritis. Adanya mutasi dalam gen prokolagen atau gen-gen struktural lain untuk unsur-unsur tulang rawan sendi seperti kolagen, proteoglikan berperan dalam timbulnya kecenderungan familial pada osteoartritis.10c. Faktor Gaya Hidup1) Kebiasaan Merokok Merokok dapat merusak sel dan menghambat proliferasi sel tulang rawan sendi. Merokok dapat meningkatkan tekanan oksidan yang mempengaruhi hilangnya tulang rawan. Merokok dapat meningkatkan kandungan karbonmonoksida dalam darah, menyebabkan jaringan kekurangan oksigen dan dapat menghambat pembentukan tulang rawan.122) Konsumsi Vitamin DOrang yang tidak biasa mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D memiliki peningkatan risiko 3 kali lipat menderita OA lutut.13d. Faktor Metabolik1) ObesitasBerat badan yang berlebih ternyata dapat meningkatkan tekanan mekanik pada sendi penahan beban tubuh, dan lebih sering menyebabkan osteoartritis lutut.7 2) OsteoporosisHubungan antara OA lutut dan osteoporosis mendukung teori bahwa gerakan mekanis yang abnormal tulang akan mempercepat kerusakan tulang rawan sendi.103) Penyakit LainOA lutut terbukti berhubungan dengan diabetes mellitus, hipertensi dan hiperurikemi, dengan catatan pasien tidak mengalami obesitas.104) HisterktomiHal ini diduga berkaitan dengan pengurangan produksi hormon estrogen setelah dilakukan pengangkatan rahim. 105) ManisektomiMenisektomi merupakan operasi yang dilakukan di daerah lutut dan telah diidentifikasi sebagai faktor risiko penting bagi OA lutut. Hal ini berkaitan dengan hilangnya jaringan meniscus.14
2. Faktor Biomekanisa. Riwayat Trauma LututTrauma lutut yang akut termasuk robekan pada ligamentum krusiatum dan meniskus merupakan faktor risiko timbulnya OA lutut.9b. Kelainan AnatomisFaktor risiko timbulnya OA lutut antara lain kelainan lokal pada sendi lutut seperti genu varum, genu valgus, Legg Calve Perthes disease dan displasia asetabulum.10c. PekerjaanOsteoartritis banyak ditemukan pada pekerja fisik berat, terutama yang banyak menggunakan kekuatan yang bertumpu pada lutut (petani, kuli, dll).9d. Aktivitas FisikAktivitas fisik berat seperti berdiri lama (2 jam atau lebih setiap hari), berjalan jarak jauh (2 jam atau lebih setiap hari), mengangkat barang berat (10 kg 50 kg selama 10 kali atau lebih setiap minggu), mendorong objek yang berat (10 kg 50 kg selama 10 kali atau lebih setiap minggu), naik turun tangga setiap hari merupakan faktor risiko OA lutut. 9e. Kebiasaan Olahraga Atlit olah raga benturan keras dan membebani lutut seperti sepak bola, lari maraton dan kung fu memiliki risiko meningkat untuk menderita OA lutut.10
VII. Kriteria Diagnosis Osteoartritis Lutut (Genu)Kriteria diagnosis OA lutut menggunakan kriteria klasifikasi American College of Rheumatology seperti tercantum pada tabel berikut ini :16Tabel 2.2 Kriteria Klasifikasi Osteoartritis Lutut
Derajat osteoartritis lutut dinilai menjadi lima derajat oleh Kellgren dan Lawrence, yaitu :17 Derajat 0: tidak ada gambaran osteoartritis. Derajat 1: osteoartritis meragukan dengan gambaran sendi normal, tetapi terdapat osteofit minimal. Derajat 2: osteoartritis minimal dengan osteofit pada 2 tempat, tidak terdapat sklerosis dan kista subkondral, serta celah sendi baik. Derajat 3: osteoartritis moderat dengan osteofit moderat, deformitas ujung tulang, dan celah sendi sempit. Derajat 4: osteoartritis berat dengan osteofit besar, deformitas ujung tulang, celah sendi hilang, serta adanyasklerosis dan kista subkondral.
VIII. Penatalaksanaan OsteoarthritisTujuan penatalaksanaan pasien dengan osteoarthritis adalah:181. Meredakan nyeri2. Mengoptimalkan fungsi sendi3. Mengurangi ketergantungan kepada orang lain dan meningkatkan kualitas hidup4. Menghambat progresivitas penyakit5. Mencegah terjadinya komplikasi
Pilar terapi pada pasien dengan osteoarthritis yaitu:Nonfarmakologis:1. Modifikasi pola hidup2. Edukasi3. Istirahat teratur yang bertujuan mengurangi penggunaan beban pada sendi4. Modifikasi aktivitas5. Menurunkan berat badan6. Rehabilitasi medik/ fisioterapia. Latihan statis dan memperkuat otot-ototb. Fisioterapi, yang berguna untuk mengurangi nyeri, menguatkan otot, dan menambah luas pergerakan sendi7. Penggunaan alat bantu.Farmakologis:1. Sistemika. Analgetik Non narkotik: parasetamol Opioid (kodein, tramadol)b. Antiinflamasi nonsteroid (NSAIDs) Oral Injeksi Suppositoriac. DMOADs (disease modifying OA drugs)Diantara nutraceutical yang saat ini tersedia di Indonesia adalah Glucosamine sulfate dan Chondroitine sulfate.2. Topikala. Krim rubefacients dan capsaicin.Beberapa sediaan telah tersedia di Indonesia dengan cara kerja pada umumnya bersifat counter irritant.b. Krim NSAIDsBeberapa yang dapat digunakan adalah gel piroxicam, dan sodium diklofenak.3. Injeksi intraartikular/intra lesiPada dasarnya ada 2 indikasi suntikan intra artikular yakni penanganan simtomatik dengan steroid, dan viskosuplementasi dengan hyaluronan untuk modifikasi perjalanan penyakit. Beberapa preparat injeksi intraartikular, diantaranya :a. Steroid ( triamsinolone hexacetonide dan methyl prednisolone )Hanya diberikan jika ada satu atau dua sendi yang mengalami nyeri dan inflamasi yang kurang responsif terhadap pemberian NSAIDs, tak dapat mentolerir NSAIDs atau ada komorbiditas yang merupakan kontra indikasi terhadap pemberian NSAIDs. Dosis untuk sendi besar seperti lutut 40-50 mg/injeksi, sedangkan untuk sendi-sendi kecil biasanya digunakan dosis 10 mg.b. Hyaluronan: high molecular weight dan low molecular weightDiberikan berturut-turut 5 sampai 6 kali dengan interval satu minggu masing-masing 2 sampai 2,5 ml Hyaluronan. Sediaan di Indonesia diantaranya adalah Hyalgan danOsflex.4. PembedahanSebelum diputuskan untuk terapi pembedahan, harus dipertimbangkan terlebih dahulu risiko dan keuntungannya. Pertimbangan dilakukan tindakan operatif bila :
a. Deformitas menimbulkan gangguan mobilisasib. Nyeri yang tidak dapat teratasi dengan penganan medikamentosa dan rehabilitatifAda 2 tipe terapi pembedahan : Realignment osteotomi dan replacement joint.Macam-macam operasi sendi lutut untuk osteoarthritis :a. Partial replacement/unicompartementalb. High tibial osteotomy : orang mudac. Patella & condyle resurfacingd. Minimally constrained total replacement : stabilitas sendi dilakukan sebagian oleh ligament asli dan sebagian oleh sendi buatan.e. Cinstrained joint : fixed hinges : dipakai bila ada tulang hilang dan severe instability.f. Total knee replacement,apabila didapatkan nyeri, deformitas, instability akibat dari rheumatoid atau osteoarthritis.
Gambar 2.1 Piramida Penatalaksanaan Osteoartritis
HIPERTENSI
I. Definisi 24Hipertensi adalah tekanan darah arterial tinggi dengan berbagai kriteria sebagai batasannya, berkisar dari sistolik 140 mmHg dan diastolik 90 mmHg hingga setinggi sistolik 200 mmHg dan diastolik 110 mmHg. Pada tahun 2004, Federal Bureau of Prisons Clinical Pratice Guidelines mendefinisikan hipertensi sebagai peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mmHg atau lebih, tekanan diastolik sedikitnya 90 mmHg atau lebih.II. Etiologi 24a. Hipertensi esensial, penyebab hipertensi tidak diketahui (90/95%)b. Hipertensi Sekunder, disebabkan oleh gangguan ginjal, gangguan endokrin,gangguan neurologi, faktor psikososial, kehamilan eklamsi dan preeklamsi.III. Klasifikasi24Menurut The Seventh Report of The Joint National Commite on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Presure (JNC 7) klasifikasi tekanan darah pada orang dewasa terbagi menjadi kelompok normal, prehipertensi, hipertensi derajat 1 dan derajat 2 (Tabel 1).Tabel 1. Klasifikasi Tekanan Darah menurut JNC 7Klasifikasi Tekanan Darah menurut JNC 7
Klasifikasi Tekanan DarahTDS* (mm Hg)TDD** (mm Hg)
Nomal< 120Dan< 80
Prehipertensi120 139Atau80 89
Hipertensi derajat 1140 159Atau90 99
Hipertensi derajat 2 160Atau 100
* TDS = Tekanan Darah Sistolik, **TDD = Tekanan Darah Diastolik
IV. Faktor Risiko Hipertensi1. Faktor yang tidak dapat diubah/dikontrol1. UmurHipertensi erat kaitannya dengan umur, semakin tua seseorang semakin besar risiko terserang hipertensi. Umur lebih dari 40 tahun mempunyai risiko terkena hipertensi. Dengan bertambahnya umur, risiko terkena hipertensi lebih besar sehingga prevalensi hipertensi dikalangan usia lanjut cukup tinggi yaitu sekitar 40 % dengan kematian sekitar 50 % diatas umur 60 tahun. Arteri kehilangan elastisitasnya atau kelenturannya dan tekanan darah seiring bertambahnya usia, kebanyakan orang hipertensinya meningkat ketika 50an dan 60an.24Dengan bertambahnya umur, risiko terjadinya hipertensi meningkat. Meskipun hipertensi bisa terjadi pada segala usia, namun paling sering dijumpai pada orang berusia 35 tahun atau lebih. Sebenarnya wajar bila tekanan darah sedikit meningkat dengan bertambahnya umur. Hal ini disebabkan oleh perubahan alami pada jantung, pembuluh darah dan hormon. Tetapi bila perubahan tersebut disertai faktor-faktor lain maka bisa memicu terjadinya hipertensi.231. Jenis Kelamin Bila ditinjau perbandingan antara wanita dan pria, ternyata terdapat angka yang cukup bervariasi. Dari laporan Sugiri di Jawa Tengah didapatkan angka prevalensi 6,0% untuk pria dan 11,6% untuk wanita. Prevalensi di Sumatera Barat 18,6% pria dan 17,4% perempuan, sedangkan daerah perkotaan di Jakarta (Petukangan) didapatkan 14,6% pria dan 13,7% wanita.241. Riwayat KeluargaMenurut Nurkhalida, orang-orang dengan sejarah keluarga yang mempunyai hipertensi lebih sering menderita hipertensi. Riwayat keluarga dekat yang menderita hipertensi (faktor keturunan) juga mempertinggi risiko terkena hipertensi terutama pada hipertensi primer. Keluarga yang memiliki hipertensi dan penyakit jantung meningkatkan risiko hipertensi 2-5 kali lipat. Jika kedua orang tua kita mempunyai hipertensi, kemungkunan kita mendapatkan penyakit tersebut 60%.211. GenetikPeran faktor genetik terhadap timbulnya hipertensi terbukti dengan ditemukannya kejadian bahwa hipertensi lebih banyak pada kembar monozigot (satu sel telur) daripada heterozigot (berbeda sel telur). Seorang penderita yang mempunyai sifat genetik hipertensi primer (esensial) apabila dibiarkan secara alamiah tanpa intervensi terapi, bersama lingkungannya akan menyebabkan hipertensinya berkembang dan dalam waktu sekitar 30-50 tahun akan timbul tanda dan gejala.22
1. Faktor yang dapat diubah/dikontrol1. Kebiasaan MerokokRokok juga dihubungkan dengan hipertensi. Hubungan antara rokok dengan peningkatan risiko kardiovaskuler telah banyak dibuktikan. Selain dari lamanya, risiko merokok terbesar tergantung pada jumlah rokok yang dihisap perhari. Seseoramg lebih dari satu pak rokok sehari menjadi 2 kali lebih rentan hipertensi dari pada mereka yang tidak merokok.24Zat-zat kimia beracun, seperti nikotin dan karbon monoksida yang diisap melalui rokok, yang masuk kedalam aliran darah dapat merusak lapisan endotel pembuluh darah arteri dan mengakibatkan proses aterosklerosis dan hipertensi.241. Konsumsi Asin/GaramGaram merupakan faktor yang sangat penting dalam patogenesis hipertensi. Hipertensi hampir tidak pernah ditemukan pada suku bangsa dengan asupan garam yang minimal. Asupan garam kurang dari 3 gram tiap hari menyebabkan prevalensi hipertensi yang rendah, sedangkan jika asupan garam antara 5-15 gram perhari prevalensi hipertensi meningkat menjadi 15-20 %. Pengaruh asupan terhadap timbulnya hipertensi terjadi melalui peningkatan volume plasma, curah jantung dan tekanan darah.13Garam menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh, karena menarik cairan diluar sel agar tidak keluar, sehingga akan meningkatkan volume dan tekanan darah. Pada manusia yang mengkonsumsi garam 3 gram atau kurang ditemukan tekanan darah rata-rata rendah, sedangkan asupan garam sekitar 7-8 gram tekanan darahnya rata-rata lebih tinggi. Konsumsi garam yang dianjurkan tidak lebih dari 6 gram/hari setara dengan 110 mmol natrium atau 2400 mg/hari.21Menurut Alison Hull, penelitian menunjukkan adanya kaitan antara asupan natrium dengan hipertensi pada beberapa individu. Asupan natrium akan meningkat menyebabkan tubuh meretensi cairan yang meningkatkan volume darah.241. Konsumsi Lemak JenuhKebiasaan konsumsi lemak jenuh erat kaitannya dengan peningkatan berat badan yang berisiko terjadinya hipertensi. Konsumsi lemak jenuh juga meningkatkan risiko aterosklerosis yang berkaitan dengan kenaikan tekanan darah. Penurunan konsumsi lemak jenuh, terutama lemak dalam makanan yang bersumber dari hewan dan peningkatan konsumsi lemak tidak jenuh secukupnya yang berasal dari minyak sayuran, biji-bijian dan makanan lain yang bersumber dari tanaman dapat menurunkan tekanan darah.241. Penggunaan JelantahJelantah adalah minyak goreng yang sudah lebih dari satu kali dipakai untuk menggoreng, dan minyak goreng ini merupakan minyak yang telah rusak. Bahan dasar minyak goreng bisa bermacam-macam seperti kelapa, sawit, kedelai, jagung dan lain-lain. Meskipun beragam, secara kimia isi kendungannya sebetulnya tidak jauh berbeda, yakni terdiri dari beraneka asam lemak jenuh (ALJ) dan asam lemak tidak jenuh (ALTJ). Dalam jumlah kecil terdapat lesitin, cephalin, fosfatida, sterol, asam lemak bebas, lilin, pigmen larut lemak, karbohidrat dan protein. Hal yang menyebabkan berbeda adalah komposisinya, minyak sawit mengandung sekitar 45,5% ALJ yang didominasi oleh lemak palmitat dan 54,1% ALTJ yang didominasi asam lemak oleat sering juga disebut omega-9. minyak kelapa mengadung 80% ALJ dan 20% ALTJ, sementara minyak zaitun dan minyak biji bunga matahari hampir 90% komposisinya adalah ALTJ.201. Kebiasaan Konsumsi Minum Minuman BeralkoholAlkohol juga dihubungkan dengan hipertensi. Peminum alkohol berat cenderung hipertensi meskipun mekanisme timbulnya hipertensi belum diketahui secara pasti. Orangorang yang minum alkohol terlalu sering atau yang terlalu banyak memiliki tekanan yang lebih tinggi dari pada individu yang tidak minum atau minum sedikit.24Menurut Ali Khomsan konsumsi alkohol harus diwaspadai karena survei menunjukkan bahwa 10 % kasus hipertensi berkaitan dengan konsumsi alkohol. Mekanisme peningkatan tekanan darah akibat alkohol masih belum jelas. Namun diduga, peningkatan kadar kortisol dan peningkatan volume sel darah merah serta kekentalan darah merah berperan dalam menaikkan tekanan darah.231. ObesitasObesitas erat kaitannya dengan kegemaran mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi lemak. Obesitas meningkatkan risiko terjadinya hipertensi karena beberapa sebab. Makin besar massa tubuh, makin banyak darah yang dibutuhkan untuk memasok oksigen dan makanan ke jaringan tubuh. Ini berarti volume darah yang beredar melalui pembuluh darah menjadi meningkat sehingga memberi tekanan lebih besar pada dinding arteri. Kelebihan berat badan juga meningkatkan frekuensi denyut jantung dan kadar insulin dalam darah. Peningkatan insulin menyebabkan tubuh menahan natrium dan air.20Berat badan dan indeks Massa Tubuh (IMT) berkorelasi langsung dengan tekanan darah, terutama tekanan darah sistolik. Risiko relatif untuk menderita hipertensi pada orang obes 5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan seorang yang berat badannya normal. Pada penderita hipertensi ditemukan sekitar 20-30 % memiliki berat badan lebih.211. OlahragaKurangnya aktifitas fisik meningkatkan risiko menderita hipertensi karena meningkatkan risiko kelebihan berat badan. Orang yang tidak aktif juga cenderung mempunyai frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi sehingga otot jantungnya harus bekerja lebih keras pada setiap kontraksi. Makin keras dan sering otot jantung harus memompa, makin besar tekanan yang dibebankan pada arteri.15
1. StresStres dapat meningkatkan tekanan darah untuk sementara waktu dan bila stres sudah hilang tekanan darah bisa normal kembali. Peristiwa mendadak menyebabkan stres dapat meningkatkan tekanan darah, namun akibat stress berkelanjutan yang dapat menimbulkan hipertensi belum dapat dipastikan.111. Penggunaan EstrogenEstrogen meningkatkan risiko hipertensi tetapi secara epidemiologi belum ada data apakah peningkatan tekanan darah tersebut disebabkan karena estrogen dari dalam tubuh atau dari penggunaan kontrasepsi hormonal estrogen. MN Bustan menyatakan bahwa dengan lamanya pemakaian kontrasepsi estrogen ( 12 tahun berturut-turut), akan meningkatkan tekanan darah perempuan.20
V. Patogenesis HipertensiTekanan yang dibutuhkan untuk mengalirkan darah melalui sistem sirkulasi dilakukan oleh aksi memompa dari jantung (cardiac output/CO) dan dukungan dari arteri (peripheral resistance/PR). Fungsi kerja masing-masing penentu tekanan darah ini dipengaruhi oleh interaksi dari berbagai faktor yang kompleks. Hipertensi sesungguhnya merupakan abnormalitas dari faktor-faktor tersebut, yang ditandai dengan peningkatan curah jantung dan / atau ketahanan periferal.17
AutoregulationFunctionalconstrictionContractabilityStructuralhypertrophyBLOOD PRESURE = CARDIAC OUTPUTHypertension = Increased COPreloadPERIPHERAL RESISTANCEIncreased PRXAnd/orExces sodium intakeGenetic alterationReduce nephrone numberEndotelium derived factorsstressRenal sodium retentionCellmembranealterationRenin -angiotensinexcessSympatheticnervousoveractivityDecreasedFiltration surfaceFluidvolumeobesityHyperinsulinemiaVenousconstiction
Gambar 1. Beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan darah.20
VII Gejala Klinis HipertensiMenurut Elizabeth J. Corwin, sebagian besar tanpa disertai gejala yang mencolok dan manifestasi klinis timbul setelah mengetahui hipertensi bertahun-tahun berupa:1. Nyeri kepala saat terjaga, kadang-kadang disertai mual dan muntah, akibat tekanan darah intrakranium.1. Penglihatan kabur akibat kerusakan retina karena hipertensi.1. Ayunan langkah tidak mantap karena kerusakan susunan syaraf.1. Nokturia karena peningkatan aliran darah ginjal dan filtrasi glomerolus.1. Edema dependen akibat peningkatan tekanan kapiler.24VI. Diagnosis HipertensiMenurut Slamet Suyono, evaluasi pasien hipertensi mempunyai tiga tujuan: 1. Mengidentifikasi penyebab hipertensi.1. Menilai adanya kerusakan organ target dan penyakit kardiovaskuler, beratnya penyakit, serta respon terhadap pengobatan.1. Mengidentifikasi adanya faktor risiko kardiovaskuler yang lain atau penyakit penyerta, yang ikut menentukan prognosis dan ikut menentukan panduan pengobatan.24Data yang diperlukan untuk evaluasi tersebut diperoleh dengan cara anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan penunjang. Peninggian tekanan darah kadang sering merupakan satu-satunya tanda klinis hipertensi sehingga diperlukan pengukuran tekanan darah yang akurat. Berbagai faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran seperti faktor pasien, faktor alat dan tempat pengukuran.24Anamnesis yang dilakukan meliputi tingkat hipertensi dan lama menderitanya, riwayat dan gejala-gejala penyakit yang berkaitan seperti penyakit jantung koroner, penyakit serebrovaskuler dan lainnya. Apakah terdapat riwayat penyakit dalam keluarga, gejala yang berkaitan dengan penyakit hipertensi, perubahan aktifitas atau kebiasaan (seperti merokok, konsumsi makanan, riwayat dan faktor psikososial lingkungan keluarga, pekerjaan, dan lain-lain). Dalam pemeriksaan fisik dilakukan pengukuran tekanan darah dua kali atau lebih dengan jarak dua menit, kemudian diperiksa ulang dengan kontrolatera.24
VIII. Pengukuran Tekanan DarahMenurut Roger Watson, tekanan darah diukur berdasarkan berat kolum air raksa yang harus ditanggungnya. Tingginya dinyatakan dalam millimeter. Tekanan darah arteri yang normal adalah 110-120 (sistolik) dan 65-80 mm (diastolik). Alat untuk mengukur tekanan darah disebut spigmomanometer. Ada beberapa jenis spigmomanometer, tetapi yang paling umum terdiri dari sebuah manset karet, yang dibalut dengan bahan yang difiksasi disekitarnya secara merata tanpa menimbulkan konstriksi. Sebuah tangan kecil dihubungkan dengan manset karet ini. Dengan alat ini, udara dapat dipompakan kedalamnya, mengembangkan manset karet tersebut dan menekan akstremita dan pembuluh darah yang ada didalamnya. Bantalan ini juga dihubungkan juga dengan sebuah manometer yang mengandung air raksa sehingga tekanan udara didalamnya dapat dibaca sesuai skala yang ada.20Untuk mengukur tekanan darah, manset karet difiksasi melingkari lengan dan denyut pada pergelangan tangan diraba dengan satu tangan, sementara tangan yang lain digunakan untuk mengembangkan manset sampai suatu tekanan, dimana denyut arteri radialis tidak lagi teraba. Sebuah stetoskop diletakkan diatas denyut arteri brakialis pada fosa kubiti dan tekanan pada manset karet diturunkan perlahan dengan melonggarkan katupnya. Ketika tekanan diturunkan, mula-mula tidak terdengar suara, namun ketika mencapai tekanan darah sistolik terdengar suara ketukan (tapping sound) pada stetoskop (Korotkoff fase I). Pada saat itu tinggi air raksa didalam namometer harus dicatat. Ketika tekanan didalam manset diturunkan, suara semakin keras sampai saat tekanan darah diastolik tercapai, karakter bunyi tersebut berubah dan meredup (Korotkoff fase IV). Penurunan tekanan manset lebih lanjut akan menyebabkan bunyi menghilang sama sekali (Korotkoff fase V). Tekanan diastolik dicatat pada saat menghilangnya karakter bunyi tersebut.23Menurut Lany Gunawan, dalam pengukuran tekanan darah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:1. Pengukuran tekanan darah boleh dilaksanakan pada posisi duduk ataupun berbaring. Namun yang penting, lengan tangan harus dapat diletakkan dengan santai.1. Pengukuran tekanan darah dalam posisi duduk, akan memberikan angka yang agak lebih tinggi dibandingkan dengan posisi berbaring meskipun selisihnya relatif kecil.1. Tekanan darah juga dipengaruhi kondisi saat pengukuran. Pada orang yang bangun tidur, akan didapatkan tekanan darah paling rendah. Tekanan darah yang diukur setelah berjalan kaki atau aktifitas fisik lain akan memberi angka yang lebih tinggi. Di samping itu, juga tidak boleh merokok atau minum kopi karena merokok atau minum kopi akan menyebabkan tekanan darah sedikit naik.1. Pada pemeriksaan kesehatan, sebaiknya tekanan darah diukur 2 atau 3 kali berturut-turut, dan pada detakan yang terdengar tegas pertama kali mulai dihitung. Jika hasilnya berbeda maka nilai yang dipakai adalah nilai yang terendah.1. Ukuran manset harus sesuai dengan lingkar lengan, bagian yang mengembang harus melingkari 80 % lengan dan mencakup dua pertiga dari panjang lengan atas.23
IX. Penatalaksanaan Hipertensi1. Penatalaksanaan Non FarmakologisPendekatan nonfarmakologis merupakan penanganan awal sebelum penambahan obat-obatan hipertensi, disamping perlu diperhatikan oleh seorang yang sedang dalam terapi obat. Sedangkan pasien hipertensi yang terkontrol, pendekatan nonfarmakologis ini dapat membantu pengurangan dosis obat pada sebagian penderita. Oleh karena itu, modifikasi gaya hidup merupakan hal yang penting diperhatikan, karena berperan dalam keberhasilan penanganan hipertensi.21Pendekatan nonfarmakologis dibedakan menjadi beberapa hal:1. Menurunkan faktor risiko yang menyebabkan aterosklerosis.Menurut Corwin berhenti merokok penting untuk mengurangi efek jangka panjang hipertensi karena asap rokok diketahui menurunkan aliran darah ke berbagai organ dan dapat meningkatkan beban kerja jantung. Selain itu pengurangan makanan berlemak dapat menurunkan risiko aterosklerosis.24Penderita hipertensi dianjurkan untuk berhenti merokok dan mengurangi asupan alkohol. Berdasarkan hasil penelitian eksperimental, sampai pengurangan sekitar 10 kg berat badan berhubungan langsung dengan penurunan tekanan darah rata-rata 2-3 mmHg per kg berat badan.211. Olahraga dan aktifitas fisikSelain untuk menjaga berat badan tetap normal, olahraga dan aktifitas fisik teratur bermanfaat untuk mengatur tekanan darah, dan menjaga kebugaran tubuh. Olahraga seperti jogging, berenang baik dilakukan untuk penderita hipertensi. Dianjurkan untuk olahraga teratur, minimal 3 kali seminggu, dengan demikian dapat menurunkan tekanan darah walaupun berat badan belum tentu turun.21Olahraga yang teratur dibuktikan dapat menurunkan tekanan perifer sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Olahraga dapat menimbulkan perasaan santai dan mengurangi berat badan sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Yang perlu diingat adalah bahwa olahraga saja tidak dapat digunakan sebagai pengobatan hipertensi.23Menurut Dede Kusmana, beberapa patokan berikut ini perlu dipenuhi sebelum memutuskan berolahraga, antara lain: 1. Penderita hipertensi sebaiknya dikontrol atau dikendalikan tanpa atau dengan obat terlebih dahulu tekanan darahnya, sehingga tekanan darah sistolik tidak melebihi 160 mmHg dan tekanan darah diastolik tidak melebihi 100 mmHg. 1. Alangkah tepat jika sebelum berolahraga terlebih dahulu mendapat informasi mengenai penyebab hipertensi yang sedang diderita. 1. Sebelum melakukan latihan sebaiknya telah dilakukan uji latih jantung dengan beban (treadmill/ergometer) agar dapat dinilai reaksi tekanan darah serta perubahan aktifitas listrik jantung (EKG), sekaligus menilai tingkat kapasitas fisik.1. Pada saat uji latih sebaiknya obat yang sedang diminum tetap diteruskan sehingga dapat diketahui efektifitas obat terhadap kenaikan beban.1. Latihan yang diberikan ditujukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan tidak menambah peningkatan darah. 1. Olahraga yang bersifat kompetisi tidak diperbolehkan.1. Olahraga peningkatan kekuatan tidak diperbolehkan.1. Secara teratur memeriksakan tekanan darah sebelum dan sesudah latihan. 1. Salah satu dari olahraga hipertensi adalah timbulnya penurunan tekanan darah sehingga olahraga dapat menjadi salah satu obat hipertensi.1. Umumnya penderita hipertensi mempunyai kecenderungan ada kaitannya dengan beban emosi (stres). Oleh karena itu disamping olahraga yang bersifat fisik dilakukan pula olahraga pengendalian emosi, artinya berusaha mengatasi ketegangan emosional yang ada.1. Jika hasil latihan menunjukkan penurunan tekanan darah, maka dosis/takaran obat yang sedang digunakan sebaiknya dilakukan penyesuaian (pengurangan).201. Perubahan pola makan1. Mengurangi asupan garamPada hipertensi derajat I, pengurangan asupan garam dan upaya penurunan berat badan dapat digunakan sebagai langkah awal pengobatan hipertensi. Nasihat pengurangan asupan garam harus memperhatikan kebiasaan makan pasien, dengan memperhitungkan jenis makanan tertentu yang banyak mengandung garam. Pembatasan asupan garam sampai 60 mmol per hari, berarti tidak menambahkan garam pada waktu makan, memasak tanpa garam, menghindari makanan yang sudah diasinkan, dan menggunakan mentega yang bebas garam. Cara tersebut diatas akan sulit dilaksanakan karena akan mengurangi asupan garam secara ketat dan akan mengurangi kebiasaan makan pasien secara drastis.13,211. Diet rendah lemak jenuhLemak dalam diet meningkatkan risiko terjadinya aterosklerosis yang berkaitan dengan kenaikan tekanan darah. Penurunan konsumsi lemak jenuh, terutama lemak dalam makanan yang bersumber dari hewan dan peningkatan konsumsi lemak tidak jenuh secukupnya yang berasal dari minyak sayuran, biji-bijian dan makanan lain yang bersumber dari tanaman dapat menurunkan tekanan darah.221. Memperbanyak konsumsi sayuran, buah-buahan dan susu rendah lemak.Beberapa penelitian menunjukkan bahwa beberapa mineral bermanfaat mengatasi hipertensi. Kalium dibuktikan erat kaitannya dengan penurunan tekanan darah arteri dan mengurangi risiko terjadinya stroke. Selain itu, mengkonsumsi kalsium dan magnesium bermanfaat dalam penurunan tekanan darah. Banyak konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan mengandung banyak mineral, seperti seledri, kol, jamur (banyak mengandung kalium), kacang-kacangan (banyak mengandung magnesium). Sedangkan susu dan produk susu mengandung banyak kalsium.,211. Menghilangkan stressStres menjadi masalah bila tuntutan dari lingkungan hampir atau bahkan sudah melebihi kemampuan kita untuk mengatasinya. Cara untuk menghilangkan stres yaitu perubahan pola hidup dengan membuat perubahan dalam kehidupan rutin sehari-hari dapat meringankan beban stres.
1. Penatalaksanaan FarmakologisJenis-jenis obat antihipertensi untuk terapi farmakologis hipertensi yang dianjurkan oleh JNC 7:1. Diuretic, terutama jenis Thiazide (Thiaz) Aldosteron Antagonist (Ald Ant)1. Beta Blocker (BB)1. Calcium channel blocker atau Calcium antagonist (CCB)1. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACEI)1. Angiotensin II Receptor Blocker atau AT1 Receptor angiotensint/ blocker (ARB).2
Tabel 4.Indikasi dan Kontraindikasi Kelas-kelas utama Obat Antihipertensi Menurut ESH. Kelas obatIndikasiKontraindikasi
MutlakTidak mutlak
Diuretika (Thiazide)Gagal jantung kongestif, usia lanjut, isolated systolic hypertension, ras afrikagoutkehamilan
Diuretika (loop)
Diuretika (anti aldosteron) penyekat Insufisiensi ginjal, gagal jantung kongestif Gagal jantung kongestif, pasca infark miokardiumAngina pectoris, pasca infark myocardium gagal jantung kongestif, kehamilan, takiaritmia
Gagal ginjal, hiperkalemia
Asma, penyakit paru obstruktif menahun, A-V block
Penyakit pembuluh darah perifer, intoleransi glukosa, atlit atau pasien yang aktif secara fisik
Calcium Antagonist (dihydropiridine)
Calcium Antagonist (verapamil, diltiazem)Usia lanjut, isolated systolic hypertension, angina pectoris, penyakit pembuluh darah perifer, aterosklerosis karotis, kehamilanAngina pectoris, aterosklerosis karotis, takikardia supraventrikuler
A-V block, gagal jantung kongestifTakiaritmia, gagal jantung kongestif
Penghmbat ACE
Angiotensi II reseptor antagonist (AT1-blocker)Gagal jantung kongestif, disfungsi ventrikel kiri, pasca infark myocardium, non-diabetik nefropati, nefropati DM tipe 1, proteinuriaNefropati DM tipe 2, mikroalbumiuria diabetic, proteinuria, hipertrofi ventrikel kiri, batuk karena ACEIKehamilan, hiperkalimea, stenosis arteri renalis bilateral
Kehamilan, hiperkalemia, stenosis arteri renalis bilateral
-BlockerHyperplasia prostat (BPH), hiperlipidemiaHipotensi ortostatisGagal jantung kongestif
Indikasi dan Kontraindikasi Kelas-kelas utama Obat Antihipertensi.21Adapun Tatalaksana hipertensi menurut menurut JNC7 dapat dilihat pada tebel 5 dibawah ini : Tabel 5. Tatalaksana hipertensi menurut menurut JNC7
Klasifikasi Tekanan DarahTDS (mmHg)TDD (mmHg)Perbaikan Pola HidupTanpa indikasi yang memaksaDengan indikasi yang memaksa
Normal
< 120
Dan