Modul
-
Upload
avindha-amnichyetha -
Category
Documents
-
view
21 -
download
11
description
Transcript of Modul

PETUNJUK PRAKTIKUM
AGROMETEOROLOGI
2015
LABORATORIUM AGROKLIMATOLOGI
JURUSAN TANAH FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JEMBER
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI i

TIM PENGAMPU MATAKULIAH
DOSEN Dr. Ir. CAHYOADI BOWO Ir. USMADI, MP.
Ir. IRWAN SADIMAN, MS.
Dr. Ir. JOSI ALI ARIFANDI, MS. Dr. Ir. TARSICIUS SUTIKNO, M. Sc. Ir. JOKO SUDIBYA, M.Si.
Ir. MARGA MANDALA, MS., PhD.
ASISTEN LABORATORIUM
AULIA CHOIRUN NISA
FEBBY MARDHIANA
FITRIA RETNO SARI
GIAN DEVARA K. V. INDAH SAFITRI RUTH ELIKA CAHYANTI
TEKNISI LABORATORIUM
HELY SETYONO
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI i

KATA PENGANTAR
Cuaca dan iklim merupakan fenomena alam yang kehadirannya sangat diperlukan
dalam kegiatan bidang pertanian. Semakin beragam dan tidak menentunya pola cuaca saat ini
akibat fenomena perubahan iklim global semakinmenuntutpemahaman dan penguasaan yang
baik bagi setiap orang yang terlibat dalam kegiatan bidang pertanian, termasuk para
mahasiswa Fakultas Pertanian. Penguasaan dan pemahaman unsur iklim bagi mahasiswa
tidak hanya dalam bentuk teori semata, tetapi mahasiswa harus mampu mengetahui,
memahami dan mengimplementasikannya dalam bentuk praktis. Terkait dengan hal
tersebut,maka kegiatan praktikum Agrometeorologi harus diarahkan sesuai dengan target
yang diharapkan. Untuk itu kiranya perlu dibuat panduan praktikum yang diberi nama
Petunjuk Praktikum Agrometeorologi.
Petunjuk praktikum ini terdiri atas beberapa acara praktikum yang telah disusun
sedemikian rupa, sehingga selain mudah dipahami juga diharapkan dapat menunjang kegiatan
perkuliahan karena telah dilakukan sinkronisasi antara materi praktikum dan perkuliahan.
Kehadiran Petunjuk Praktikum ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan
mahasiswa dalam mengikuti praktikum Agrometeorologi, sehingga dapat menunjang
kelancaran mahasiswa dalam memahami peran dan kemanfaatan berbagai elemen cuaca
dalam bidang pertanian.
Tim penyusun sudah berusaha sebaik mungkin dalam menyajikan penuntun
praktikum ini. Namun demikian adanya kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan
demi perbaikan selanjutnya. Akhirnya Tim Penyusun berharap semoga Petunjuk Praktikum
ini dapat memberikan manfaat bagi penggunanya.
Jember, September 2015
Tim Penyusun
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI ii

TATA TERTIB PRAKTIKUM
1. Praktikan diwajibkan hadir 10 menit sebelum rangkaian acara praktikum dimulai. Praktikan yang terlambat hadir sampai batas waktu dimulainya praktikum dianggap tidak mengikuti kegiatan acara praktikum yang sedang berlangsung.
2. Praktikan yang tidak mengikuti satu atau lebih acara praktikum diwajibkan mengikuti
praktikum susulan (inhaln) dan susulan untuk setiap acara praktikum hanya dilangsungkan satu periode praktikum.
3. Praktikan diwajibkan memakai baju berkerah (sopan) dan bersepatu selama
berlangsungnya kegiatan praktikum. 4. Setiap praktikan diwajibkan mengikuti seluruh ragkaian kegiatan praktikum dan mencatat
hasilnya sebagai laporan sementara. Laporan sementara yang mendapat persetujuan pengelola praktikum, digunakan sebagai materi utama dalam membuat laporan resmi yang dikumpulkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah acara praktikum selesai.
5. Praktikan diwajibkan mengulang apabila terjadi kesalahan dalam pengambilan,
pencatatan, pengolahan dan interpretasi data. 6. Praktikan dilarang merokok, makan, minum atau melakukan aktivitas lain yang tidak ada
kaitannya dengan acara praktikum selama berlangsungya kegiatan praktikum. 7. Praktikan diwajibkan mengikuti evaluasi akhir praktikum (responsi) dengan syarat
praktikan tidak mempunyai tanggungan kepada laboratorium. 8. Praktikan yang tidak dapat memenuhi standar kelulusan minimal praktikum tidak
diikutkan sebagai peserta ujian akhir semester (UAS). 9. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan disampaikan dan diatur kemudian.
Jember, September 2015
Pembina Kuliah dan Praktikum
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI iii

DAFTAR ISI
TIM PENGAMPU MATAKULIAH…………………………………………………… i
KATA PENGANTAR…………………………………………………………………… ii
TATA TERTIB PRAKTIKUM……………………………………………………….... iii
DAFTAR ISI…………………………………………………………………………….. iv ACARA 1 : PENGENALAN DAN PENGELOLAAN STASIUN IKLIM …………. 1
ACARA 2: PENCATATAN DAN PENGELOLAAN DATA IKLIM ……………… 8
ACARA 3 : ANALISIS DATA UNSUR-UNSUR IKLIM ………………………….... 11
ACARA 4 : KLASIFIKASI IKLIM DAN PENETAPAN AWAL MUSIM...………. 13 ACARA 5: NERACA AIR TANAMAN……………………………………………….. 17
ACARA 6: AKSES INFORMASI CUACA…………………………………………… 28
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI iv

ACARA 1 : PENGENALAN DAN PENGELOLAAN STASIUN CUACA
TUJUAN : 1. Mengetahui Macam dan Fungsi Instrumentasi Meteorologi Pada Stasiun Cuaca
2. Mengetahui Tatacara Pengelolaan Stasiun Cuaca
LANDASAN TEORI
Tersedianya data meteorologi yang cukup merupakan kebutuhan dasar untuk membuat
perencanaan yang baik dalam bidang pertanian. Segala kegiatan dalam proses produksi pertanian
mulai dari perencanaan sampai dengan penanganan pasca panen memerlukan tersedianya data
cuaca yang benar. Data cuaca yang diperlukan dapat diukur setiap waktu, dikumpulkan dalam
periode tertentu, kemudian diolah sesuai dengan keperluannya, oleh karena itu data yang
dikumpulkan harus dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Pengetahuan untuk
memperoleh data cuaca yang benar merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam
pengamatan unsur-unsur cuaca.
Kualitas data yang diukur pada suatu tempat tertentu, banyak dipengaruhi oleh keadaan
lingkungan, cara penempatan alat, macam peralatan dan mental pengamat. Suatu data yang baik
seharusnya dapat dibandingkan dengan data tempat lain sehingga perbedaan yang ditunjukkan
oleh data tersebut betul-betul terjadi karena kondisi cuaca bukan karena cata pengambilan data
yang salah. Suatu stasiun cuaca supaya dapat memberikan data yang dapat dipertanggung-
jawabkan setidaknya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Lokasi
Untuk memperkirakan pengaruh cuaca maupun iklim pada tanaman, letak stasiun
harus mewakili tanah-tanaman-iklim wilayah yang akan menggunakan data tersebut. Lokasi
harus mewakili watak iklim untuk wilayah yang seluas-luasnya. Tempat-tempat dimana
diketemukannya perbedaan cuaca yang jelas akibat adanya rawa, gunung, sungai atau danau
harus dihindarkan. Ukuran stasiun paling sedikit seluas 10 x 10 m2 dan dianjurkan berada
ditengah wilayah terbuka yang luasnya paling sedikit 50 x 50 m2. Permukaan tanah di dalam
stasiun sebaiknya tertutup oleh rumput atau tanaman pendek dan dianjurkan dilakukan irigasi
dan rumput harus sering dipotong. Untuk keperluan bidang pertanian sebaiknya sekitar lokasi
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI 1

stasiun ditanami dengan tanaman pertanian yang cukup luas. Lokasi stasiun juga harus dekat
dengan rumah pengamat. 2. Peralatan
Untuk studi kebutuhan air tanaman atau studi lain yang sejenis, fenomena cuaca yang
diamati antara lain kelengasan, suhu, angin, hujan lama penyinaran matahari dan evaporasi.
Dalam kaitan tersebut peralatan yang seharusnya ada dan dapat digunakan sebagaimana
dalam Tabel 1.
Tabel 1. Peralatan yang lazim terdapat di dalam Stasiun Iklim
No. Nama Alat Fungsi
1. Sangkar meteo
Berfungsi untuk menempatkan alat ukur suhu dan
lengas udara. Sangkar meteo merupakan
bangunan berbentuk rumah yang terbuat dari
kayu yang berfungsi untuk menyimpan alat
termohigrograf, termometer maksimum,
termometer minimum, termometer bola kering
dan termometer bola basah.
2. Termometer
Berfungsi untuk mengukur suhu dan pendekatan
lengas udara. Perubahan suhu sepanjang hari
dapat diketahui dengan melihat catatan suhu pada
termograf dan termometer. Suhu tertinggi biasa
terjadi pada pukul satu atau dua siang, sedangkan
suhu terendah biasa terjadi pukul empat atau lima
pagi. Dari rata-rata derajat panas sepanjang
harinya didapatkan suhu harian.
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI 2

3. Ombrometer Berfungsi untuk mengukur curah hujan. Alat
Pengukur Curah Hujan merupakan alat yang
digunakan untuk mencatat intensitas curah hujan
dalam kurun waktu tertentu. Hasil pencatatan
curah hujan pada umumnya dihubungkan dengan
hasil pencatatan pergerakan tanah pada
extensometer. Hasil pencatatan alat pengukur
curah hujan dapat digunakan sebagai pembanding
dengan hasil pencatatan pergerakan tanah pada
extensometer yang dapat dinyatakan bahwa
semakin besar intensitas curah hujan, maka tanah
cenderung mudah bergerak
4. Anemometer Berfungsi untuk mengukur kecepatan angin dan
untuk mengukur arah. Anemometer merupakan
salah satu instrumen yang sering digunakan oleh
balai cuaca seprti Badan Meteorologi Klimatologi
dan Geofisika (BMKG). Kata anemometer berasal
dari Yunani anemos yang berarti angin, angin
merupakan udara yang bergerak ke segala arah,
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI 3

bergerak dari suatu tempat menuju ke tempat
yang lain.
5. Sunshine Recorder Berfungsi untuk merekam atau mengukur lama
penyinaran matahari yang terekam oleh
terbakarnya pias. Alat ini terdiri dari bola kaca dan
mangkuk logam yang mengelilingi bagian
belakang bola kaca (tipe Campbell-Stokes).
Sepotong kertas rekam yang telah dikalibrasi
kepekaannya terhadap panas dipasang pada
bagian lengkung.
6. Panci Evaporasi Kelas ABerfungsi untuk mengukur evaporasi. Evaporasi
yang diukur dengan panci ini dipengaruhi oleh
radiasi surya yang datang, kelembapan udara,
suhu udara dan besarnya angin pada tempat
pengukuran. Kesalahan terbesar dalam
pengukuran evaporasi terletak pada tinggi air
dalam panci. Oleh sebab itu muka air selamanya
harus dikembalikan pada tinggi semula yaitu 5
cm di bawah bibir panci. Makin rendah muka
air dalam panci, makin rendah pula terjadinya
penguapan. Kejernihan air dalam panci selalu
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI 4

dijaga. Dalam Air yang keruh, evaporasi yang
terukur akan rendah pula.
Khusus untuk Sunshine Recorder, maka Kertas Pias harus dipasang sesuai dengan arah posisi matahari yang selalu berubah sepanjang tahun. Terdapat 2 jenis Kertas Pias, yaitu kertas Pias Lurus dan Lengkung. Untuk daerah sekitar khatulistiwa dengan lintasan matahari relatif tegak lurus bumi dan panjang harin relatif sama sepanjang tahun, pias yang digunakan cukup satu macam, yaitu pias lurus. Untuk daerah yang terletak di lintang yang besar yang mempunyai lebih dari 2 musim, kertas pias yang digunakan ada 3 bentuk, yaitu pias lurus, pias lengkung panjang dan pias lengkung pendek. Pemasangan kertas pias diatur seperti Tabel 2.
Tabel 2. Pemasangan Kertas Pias pada Sunshine Recorder
Bentuk kertas pias Tanggal penggunaan
Belahan bumi utara Belahan bumi selatan
Lengkung panjang 11 April - 31 Agustus 11 Oktober - 28 Februari
Pias lurus 1 September - 10 Oktober 1 Maret - 10 April
Lengkung pendek 11 Oktober - 28 Februari 11 April - 31 Agustus
Pias lurus 1 Maret - 10 April 1 September - 10 Oktober
Untuk memperoleh hasil pembakaran yang sempurna, maka bola lensa perlu diatur kemiringannya sesuai dengan lintang tempat alat dipasang. Dengan demikian lengkung tempat pias akan sejajar ekuator. Sebagai contoh alat dipasang di suatu tempat dengan lintang x° Lintang Selatan (LS), maka kemiringan bila diatur x ° ke arah Utara (Gunawan Nawawi 2001).
Semua peralatan diatas sebaiknya diletakkan sedemikian rupa sehingga pemasangan alat yang satu tidak mengganggu fungsi peralatan yang lain. namun demikian suatu alat ulur dalam instrumentasi meteorologi harus memenuhi syarat; ketepatan; ketelitian; tidak rumit atau sederhana; mudah dibaca; tahan lama (kuat) dan biaya pengelolaan murah.
3. Pengamatan
Dari seluruh rangkaian kegiatan pengamatan pada suatu stasiun cuaca, waktu
pengamatan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan, karena keteraturan dan
ketepatan waktu pengamatan banya ditentukan oleh letak surya dan setiap tempat mempunyai
sistem waktu tertentu tergantung pada letak tempat di permukaan bumi.
Sistem waktu menurut tempat disebut waktu setempat (WST) sesuai dengan waktu
surya. Di Indonesia waktu yang dipakai sehari-hari adalah waktu wilayah yaitu Wilayah
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI 5

Indonesia Barat; Tengah dan Timur (WIB; WITa dan WIT) dengan perbedaan waktu masing-
masing satu jam. Untuk menentukan waktu setempat ke dalam waktu wilayah dipakai rumus
berikut ini :
WW = WST + B + K
Dengan:
WW = Waktu Wilayah
WST = Waktu setempat
B = Beda waktu
K = Koreksi waktu dalam menit
Untuk menentukan nilai B digunakan rumus sebagai berikut :
B = 4 (DWW – DBT) menit
Dengan :
DWW = Derajat Waktu Wilayah (105 untuk WIB; 120 untuk WITa; 135 untuk WIT)
DBT = Derajat Bujur Timur dari tempat yang akan ditentukan
Waktu yang telah ditentukan untuk pengamatan harus selalu dicatat pada lembar
pengamatan dan semua pengamatan harus dilakukan sedekat-dekatnya dengan waktu
pengamatan yang telah dijadwalkan.
4. Pengamat
Kesalahan orang umumnya merupakan sumber utama kesalahan data dan ini sangat
bergantung pada kemampuan dan dedikasi pengamat. Untuk menghindari kesalahan,
pengamat harus mendapat latihan yang baik terutama yang berhubungan dengan instrumentasi
meteorologi yang digunakan. Tempat tinggal pengamatan diusahakan dekat dengan stasiun
pengamatan dan sangat dianjurkan menunjuk pengamat yang akan mempunyai tugas
tambahan misalnya sebagai juru tulis.
KEGIATAN :
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI 6

1. Lakukan kunjungan ke stasiun cuaca yang telah ditentukan lokasinya 2. Amati instrumentasi yang ada pada stasiun tersebut dan pahami apa fungsi alat tersebut
3. Diskusikan hasil pengamatan saudara berkaitan dengan lokasi stasiun, kondisi instrumentasi,
cara pengambilan dan pencatatan data serta petugas pencatat data pada stasiun yang saudara
kunjungi
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI 7

ACARA 2 : PENCATATAN DAN PENGELOLAAN DATA IKLIM
TUJUAN : Mengetahui Cara Pencatatan dan Pengelolaan Data Iklim
LANDASAN TEORI
Cuaca memiliki sifat yang sangat komplek baik dalam skala ruang maupun waktu.
Gambaran mengenai cuaca dapat dilihat atau dianalisis dari data unsur-unsur cuaca. Jadi
kebenaran dan keabsahan data memegang peran yang sangat penting untuk memberi gambaran
kondisi cuaca yang akurat. Masalah pengelolaan data cuaca mencakup beberapa hal mulai dari
metode mendapatkan data, pencatatan dan pengarsipan, pengolahan, peramalan hingga penyajian
informasi iklim yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak.
Untuk keperluan kegiatan yang bersifat ilmiah maka unsur-unsur cuaca harus dinyatakan
dalam bentuk yang bersifat kuantitatif. Mengingat cuaca merupakan suatu nilai sesaat dari
atmosfer dan perubahannya dalam jangka pendek (kurang dari satu jam hingga 24 jam) di suatu
tempat tertentu, maka untuk memperoleh data unsur cuaca harus dilakukan pencatatan secara
terus menerus pada jam-jam tertentu secara rutin. Data unsur cuaca pada suatu stasiun pengamat
cuaca yang diperoleh dari pengamatan dan pencatatan yang rutin dan tertib, akan menghasilkan
suatu seri data cuaca. Seri data tersebut setelah terkumpul selama satu tahun biasanya akan
membentuk pola siklus tertentu yang selanjutnya bila telah terkumpul sekitar 30 tahun akan
mencerminkan sifat atmosfer yang dikenal sebagai iklim. Seri data itu selanjutnya disebut
dengan data iklim dan dapat digunakan untuk menentukan kondisi iklim suatu wilayah.
Mengingat iklim adalah sifat cuaca dalam jangka panjang dan pada daerah yang luas, maka
data cuaca yang digunakan untuk menyusunnya hendaklah mewakili kondisi atmosfer seluas mugkin.
Demikian pula datanya harus terhindar dari gangguan lokal yang bersifat sementara. Pada prinsipnya
data iklim harus terbentuk dari data cuaca yang dapat mewakili secara benar (representatif) keadaan
atmosfer yang luas dan dalam jangka waktu sepanjang mungkin.
Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam pengelolaan data cuaca, setiap stasiun harus
menyediakan lembar-lembar pengamatan yang baku guna mencatat hasil pengamatan. Lembar-
lembar pengamatan tersebut dapat berupa lembar pengamatan harian, mingguan, dasarian, bulanan
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI 8

dan tahunan. Lembar-lembar pengamatan tersebut akan terus terkumpul dari waktu ke waktu dan
disusun dalam bentuk yang seragam sehingga akan memudahkan pengelolaan data selanjutnya.
KEGIATAN : 1. Kunjungi stasiun cuaca yang telah ditentukan sebelumnya
2. Amati, baca dan catat secara teratur data instrumentasi meteorologi yang ada dalam jangka
waktu tertentu sesuai dengan jadwal pengamatan 3. Masukkan data hasil pengamatan ke dalam lembar pengamatan harian, kemudian kumpulkan
lembar pengamatan harian tersebut sehingga dapat menjadi satu seri data cuaca 4. Simpan seri data cuaca tersebut dan gunakan sebagai bahan praktikum pada acara selanjutnya.
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI 9

STASIUN IKLIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOKASI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Posisi Geografis ……. LS
dan …….. BT
No. Hari/TGL Jam Radiasi Surya Curah Evaporasi Suhu Max
Kelembaban Relatif
(mm) Angin - Min (0C) Hujan Keterangan Intensitas Lama (m/jam) Bola Bola RH (mm) Awal Akhir Max Min (cal) (jam) Kering Basah (%)
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI 10

ACARA 3 : ANALISIS DATA UNSUR-UNSUR IKLIM
TUJUAN : 1. Mengelompokkan Data Unsur Cuaca Berdasar Sifat dan
Karakteristiknya. 2. Menganalisis dan Menafsirkan Data Unsur-unsur Cuaca.
LANDASAN TEORI
Data cuaca atau iklim berdasar sifat dan karakteristiknya dibedakan menjadi dua
kelompok yaitu data cuaca atau iklim kontinyu dan diskontinyu. Data unsur cuaca yang sifatnya
kontinyu antara lain suhu, kelembaban udara, tekanan udara dan angin. Sedangkan data yang
sifatnya diskontinyu antara lain radiasi dan lama penyinaran surya, presipitasi dan evaporasi.
Karena sifat dan karakteristik datanya yang berbeda, maka pengelolaan dan analisis datanyapun
juga berbeda. Data-data cuaca yang sifatnya kontinyu disajikan dalam bentuk angka rata-rata
atau angka sesaat dan bila disajikan dalam bentuk gambar atau grafik bentuknya garis atau
kurva. Sedangkan data cuaca diskontinyu disajikan dalam bentuk nilai akumulasi dan bila
disajikan dalam gambar bentuknya berupa kurva histogram.
Metode statistik dan persamaan matematik dapat dimanfaatkan untuk memudahkan
mempelajari sifat cuaca maupun iklim yang kompleks. Malelui analisis statistik dan matematik
data yang rumit dapat disederhanakan, ciri-ciri unsur iklim dapat dipelajari dan dianalisis
sehingga mempermudah penelaahan informasi yang terkandung dalam data. Dari manfaat
penggunaan analisis statistik tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan ketepatan dalam
peramalan yang akhirnya akan dapat menyediakan informasi iklim yang lengkap dan akurat.
Data cuaca yang akurat dan dapat dianalisis lebih lanjut, adalah data yang homogen atau
konsisten. Data cuaca dikatakan homogen apabila simpangan yang terdapat pada data semata-mata
hanya diakibatkan oleh simpangan cuaca/ilkim bukan oleh sebab lain. Sebab lain yang dimaksud
misalnya seperti perubahan di sekitar stasiun karena adanya bangunan baru, pohon yang semakin
besar yang mengakibatkan perubahan kondisi lokal, pembangunan prasarana lain dan sebagainya.
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI 11

KEGIATAN :
1. Siapkan data unsur cuaca harian selama satu tahun dari satu stasiun pengamat cuaca yang
telah ditentukan. 2. Sajikan data unsur cuaca tersebut dalam bentuk dasarian dan bulanan.
3. Lakukan analisis data sesuai dengan sifat dan karakteristik dari masing-masing unsur cuaca.
4. Sajikan hasil analisis saudara dalam bentuk tabel dan gambar sesuai dengan sifat-sifat unsur
cuacanya.
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI 12

ACARA 4 : KLASIFIKASI IKLIM DAN PENETAPAN AWAL MUSIM
TUJUAN : 1. Memahami Beberapa Cara Klasifikasi Iklim menurut SchmidtFergusoon dan
Oldeman, serta Kegunaannya di Bidang Pertanian.
2. Mengetahui Cara Penetapan Awal Musim dan Sifat Hujan.
LANDASAN TEORI :
Iklim merupakan gabungan berbagai kondisi cuaca sehari-hari atau merupakan rerata
cuaca, sehingga iklim tersusun atas berbagai unsur yang variasinya besar. Meskipun perilaku
iklim di bumi cukup rumit tetapi ada kecenderungan karakteristik dan pola tertentu dari unsur
iklim di berbagai daerah yang letaknya saling berjauhan bila faktor utamanya sama.
Mendasarkan atas kesamaan sifat tersebut makan dalam bidang ilmu iklim juga dikenal
pengelompokan iklim dalam kelas-kelas tertentu yang disebut dengan klasifikasi iklim.
Pada hakekatnya, kegunaan klasifikasi iklim adalah untuk memperoleh efisiensi
informasi dalam bentuk yang umum dan sederhana. Sehingga analisis statistik dalam klasifikasi
iklim dapat dilakukan untuk menjelaskan dan memberi batas pada tipe-tipe iklim secara
kuantitatif, umum dan sederhana. Sehubungan dengan itu, maka di dalam mengelompokkan atau
klasifikasi, langkah pertama yang dilakukan adalah pengelompokan berdasar pada persamaan
sifat yang besar (global) dan diikuti pada sifat yang kecil (detail) di dalam sub bagiannya.
Banyak klasifikasi iklim yang telah dibuat dan masing-masing mempunyai sistem
tersendiri sesuai dengan tujuannya. Masing-masing menggunakan unsur iklim yang berbeda
sebagai parameternya, namun demikian secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua
yaitu klasifikasi secara genetik dan klasifikasi empirik. Klasifikasi iklim genetik mendasarkan
kriterianya pada unsur iklim penyebab dan menghasilkan klasifikasi untuk pewilayahan yang
luas tapi kurang teliti. Sedangkan klasifikasi secara empirik mendasarkan atas hasil pengamatan
yang teratur dari unsur-unsur iklim dan menghasilkan klasifikasi pada pewilayahan yang sempit
tapi lebih teliti. Klasifikasi iklim banyak diginakan di Indonesia untuk bidang pertanian dalam
arti luas adalah klasifikasi menurut Schmidth – Ferguson dan klasifikasi menurut Oldeman.
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI 13

1. Sistem Klasifikasi Schmidt – Ferguson
Sistem ini banyak digunakan dalam bidang perkebunan dan kehutanan. Penetapan
tipe iklim menurut klasifikasi ini mendasarkan pada data curah hujan bulanan dan
memerlukan data hujan paling sedikit 10 tahun. Kriteria yang digunakan adalah penentuan
bulan kering (bulan dengan hujan < 60 mm), bulan lembab (bulan dengan hujan 60-100 mm)
dan bulan basah (bulan dengan hujan > 100 mm). Schmidth – Ferguson menentukan bulan
kering, bulan lembab, dan bulan basah tahun demi tahun selama periode pengamatan
kemudian dijumlahkan dan dihitung reratanya. Penentuan tipe iklim mendasarkan pada nilai
Q yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Nilai Rerata Bulan Kering
Q = --------------------------------------- x 100%
Nilai Rerata Bulan Basah
Dari perhitungan nilai Q tersebut Schmidth – Ferguson membagi tipe iklim menjadi 8
kelas yang diberi simbol huruf A sampai H, dengan rincian selengkapnya sebagai berikut: Nilai Q (%) Tipe Keterangan
< 14,3 A Daerah sangat basah dengan vegetasi hutan hujan tropik
>14,3 - <33,3 B Daerah basah dengan vegetasi masih hutan hujan tropik
>33,3 - < 60 C Daerah agak basah dengan vegetasi hutan rimba
>60 - < 100 D Daerah sedang dengan vegetasi hutan musim
>100 - <167 E Daerah agak kering dengan vegetasi hutan sabana
>167 - <300 F Daerah kering dengan vegetasi hutan sabana
>300 - <700 G Daerah sangat kering dengan vegetasi hutan ilalang
>700 H Daerah ekstrim kering dengan vegetasi hutan ilalang
2. Sistem Klasifikasi Oldeman
Sistem klasifikasi ini menghubungkan unsur iklim yaitu hujan dengan pertanian dan
banyak digunakan untuk tanaman semusim. Kriteria pengklasifikasiannya mendasarkan pada
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI 14

perhitungan bulan basah (bulan dengan hujan > 200 mm), bulan lembab (bulan dengan hujan
100-200 mm) dan bulan kering (bulan dengan hujan < 100 mm).
Tipe utama klasifikasi dibagi dalam 5 tipe yang didasarkan pada bulan basah berturut-
turut. Sedangkan sub divisinya dibagi 4 yang didasarkan pada lamanya bulan kering berturut-
turut. Rincian selengkapnya adalah sebagai berikut: Tipe Utama Bulan Basah Berturut-turut
A >9
B 7 – 9
C 5 – 6
D 3 – 4
E <3
Sub Divisi Bulan Kering Berturut-turut
1 <2
2 2 – 3
3 4 – 6
4 >6
Dari 5 tipe utama dan 4 sub divisi tersebut Oldeman mengelompokkan menjadi 17
daerah agroklimat ,ulai dari A1 sampai E4, dengan penjabaran sebagai berikut:
Tipe Iklim Keterangan
A1 : A2 Sesuai untuk padi terus menerus tapi produksi kurang karena pada
umumnya intensitas radiasi rendah sepanjang tahun
B1 Sesuai untuk padi terus menerus dengan perencanaan awal tanam
yang baik. Produksi tinggi bila panen kemarau
B2 Dapat tanam padi dua kali setahun dengan varietas umur pendek
dan musim kering yang pendek cukup untuk palawija
C1 Tanam padi sekali dan palawija dua kali setahun
C2 : C3 : C4 Setahun hanya dapat satu kali padi dan penanaman palawija yang
kedua harus hati-hati jangan jatuh pada bulan kering
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI 15

D1 Tanam padi umur pendek satu kali dan biasanya produksi bisa
tinggi. Waktu tanam palawija cukup
D2 : D3 : D4 Hanya mungkin satu kali padi atau satu kali palawija setahun
tergantung pada adanya persediaan air irigasi
Daerah ini umumnya terlalu kering, mungkin hanya satu kali
E palawija itupun bergantung adanya hujan
Selain penentuan tipe iklim seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam kaitannya
dengan data hujan ada hal lain yang mempunyai arti penting dalam bidang pertanian yaitu
penentuan awal musim hujan dan awal musim kemarau. Pengertian awal musim hujan adalah
suatu keadaan dimana curah hujan dalam satu dekade dan tiap-tiap dekade berikutnya
jumlahnya lebih besar atau sama dengan 50 mm, dan / atau dalam tiga dekade berturut-turut
lebih besar atau sama dengan 150 mm. Sedangkan yang dimaksud awal musim kemarau
adalah bila curah hujan dalam satu dekade dan tiap dekade-dekade berikutnya jumlahnya
kurang dari 50 mm, atau dalam tiga dekade berturut-turut curah hujan kurang dari 150 mm.
Selain awal musim berdasar data hujan yang ada, juga dapat ditentukan sifat hujan dalam satu
periode dibandingkan dengan sifat curah hujan normalnya. Bila nilai simpangannya berada
antara 85-115% dikatakan normal, bila berada di atas 115% dikatakan di atas normal dan bila
berada di bawah 85% berada di bawah normal.
KEGIATAN : 1. Susunlah data curah hujan yang tersedia menjadi data curah hujan dasarian dan bulanan.
2. Berdasarkan data curah hujan tersebut, tentukan tipe iklimnya berdasarkan klasifikasi Schmidt
– Ferguson dan Oldeman.
3. Berdasarkan hasil klasifikasi, tentukan jenis atau kelompok tanaman yang sesuai
dikembangkan di wilayah tersebut. 4. Tentukan pula kapan jatuhnya awal musim hujan dan musim kemarau.
5. Tentukan bagaimana sifat hujan tahun terakhir pengamatan dari data tersebut terhadap curah
hujan normalnya.
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI 16

ACARA 5 : NERACA AIR TANAMAN (CROPWAT DAN CLIMWAT)
TUJUAN : Menghitung Neraca Air Suatu Lahan Serta Penerapannya Untuk Pola Tanam
LANDASAN TEORI :
Air merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang keberhsilan usaha
pertanian. Air berada di bumi dalam keadaan dinamis yang senantiasa membentuk suatu siklus
yang dikenal dengan siklus hidrologi. Salah satu kesimpulan peting dalam siklus hidrologi
adalah bahwa jumlah air dalam suatu wilayah, dipengaruhi oleh masukan (input) dan keluaran
(output) yang terjadi. Neraca masukan dan keluaran air di suatu tempat dikenal dengan istilah
neraca air dan nilainya selalu berubah dari waktu ke waktu.
Kelebihan dan kekurangan air di suatu tempat pada suatu waktu dapat menimbulkan
bencana. Agar diperolah manfaat setinggi mungkin pada pemanfaatan air, diperlukan
perencanaan yang teliti berdasarkan neraca air. Penyusunan neraca air di suatu tempat pada suatu
periode tertentu dimaksudkan untuk mengetahui jumlah netto air yang diperoleh sehingga dapat
dimanfaatkan sebaik mungkin. Data neraca air dapat dengan cepat dan mudah memberikan
beberapa keterangan penting tentang jumlah netto air yang dapat diperoleh, nilai surplus dari air
yang tidak dapat tertampung dan kapan saat terjadinya. Berdasarkan tujuan penggunaannya,
neraca air dapat dibedakan atas neraca air umum, neraca air lahan, dan neraca air tanaman.
Neraca air umum disusun secara klimatologi dan bermanfaat untuk mengetahui
berlangsungnya periode basah (jumlah curah hujan melebihi kehilangan air untuk evapotranspirasi
potensial maupun kehilangan air keluar dari sistem pertanaman). Data yang diperlukan untuk analisis
antara lain masukan air dari curah hujan dan keluaran berupa evapotranspirasi potensial. Berdasarkan
perimbangan antara masukan dan keluaran tersebut, maka bila curah hujan melebihi evapotranspirasi
potensial maka akan terjadi kondisi surplus, sebaliknya bila curah hujan lebih kecil dari
evapotranspirasi potensial akan terjadi kondisi defisit.
Neraca air lahan disusun dengan memasukkan data dan informasi fisika tanah terutama
nilai kandungan air tanah pada kondisi kapasitas lapang dan titik layu permanen. Analisis ini
bermanfaat terutama untuk penggunaan pertanian secara umum sehingga dapat digunakan untuk
berbagai tujuan antara lain: 1. Untuk mempertimbangkan kesesuaian lahan tadah hujan bagi
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI 17

pertanian berdasar pada kandungan air tanah, 2. Mengatur jadwal tanam dan jadwal panen, 3.
Mengatur pemberian air irigasi, bail dalam jumlah maupun waktu sesuai dengan keperluan.
Neraca air pertanaman biasanya digunakan untuk tujuan spesifik pada suatu jenis
tanaman tertentu, dengan masukan nilai koefisien tanaman pada komponen keluaran dari neraca
air lahan. Model analisis neraca air pertanaman dapat ditunjukkan dengan memodifikasi nilai
evapotranspirasi potensial menurut jenis tanamannya.
Masalah yang sering dihadapi dalam membuat suatu kajian tentang keterkaitan antara
unsur-unsur iklim dengan pertanian, ialah banyaknya data yang harus dianalisis. Kondisi tersebut
menjadi lebih rumit lagi oleh adanya keterbatasan ragam data yang disediakan oleh stasiun-
stasiun pengamat iklim. Sehubungan dengan itu maka pemanfaatan peralatan seperti komputer
dan perangkat lunak penunjangnya, seakan-akan sudah menjadi keharusan untuk menganalisis
data dengan cepat dan akurat.
Seiring dengan kemajuan teknologi komputer dan multi media, telah banyak ditawarkan
berbagai ragam materi yang berkaitan dengan bidang agrometeorologi, baik dalam bentuk CD-
ROOM maupun melalui pemanfaatan program yang ada untuk kepentingan analisis data. Dengan
menggunakan bahasa program tertentu misalnya Excel maka data yang jumlahnya sangat banyak
dapat lebih cepat diolah dan dianalisis guna dicari kemanfatannya.
Selain itu adanya perangkat lunak (software) tertentu yang telah dibuat oleh para pakar,
tampaknya juga dapat menjadi pilihan dalam rangka efisiensi waktu dan tenag. Salah satu software
yang berkaitan dengan analisis neraca air, telah dikembangkan oleh FAO dengan nama program Cropwat yang merupakan kependekan dari Crop-Water Requirement. Melalui software tersebut
data yang bila dianalisis secara manual mmerlukan waktu yang lama, dapat diselesaikan dengan
cepat dan relatif mudah.
KEGIATAN
1. Berdasarkan data-data unsur cuaca dan tanah yang tersedia, buatlah neraca air umum dan
neraca air lahan. 2. Berdasarkan kondisi neraca air pada lahan tersebut, susunlah pola tanam sesuai kebutuhan
air tanaman.
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI 18

Cara kerja penggunaan Climwat dan Cropwat:
CLIMWAT 1. Buka aplikasi climwat 2. Setelah ,uncul tabel target location and country, pilih koordinat dan negara yang diinginkan. Kemudian pilih “Display all station within seleced country”
Koordinate stasiun iklim
Pilihan negara
3. Pilih wilayah atau daerah yang diinginkan untuk melihat data iklim yang ada
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI 19

Lokasi stasiun iklim Pilihan Lokasi Stasiun
Membuka dan melihat data iklim
Untuk melihat data yang ada, pilih “export”. Kemudian pilih “image atau list”→ Copy to
clipboard → “paste” pada halaman word
Pilihan Export
Mengexport Data Pilih “Export select station” → “Export PEN and CLI Files”
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI 20

Lokasi tujuan folder
Sub folder tujuan export
CROPWAT Mengimport data pada Cropwat
1. Buka aplikasi “Cropwat” 2. Pilih “Climate/ETO maka akan muncul tabel “Monthly ETO Pennan- Montetith- Untitled
Komponen informasi iklim Kolom data iklim
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI 21

3. Pilih open → pilih data yang sudah di export dari “Climwat” →Open. Maka tabel data akan
terisi data yang telah diimport
Data iklim yang sudah terisi
4. Pilih data Rain maka akan muncul tabel “Monthly Rain”
Kolom tabel data hujan
5. Pilih open → pilih data yang sudah di export dari “Climwat” →Open. Maka tabel data akan
terisi data yang telah diimport
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI 22

Pilih open untuk mengisi kolom data
6. Pilih “Crop” kemudian akan muncul tabel “ Dry Crop “
Jumlah air
Kedalaman Perakaran
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI 23

7. Pilih open → pilih data yang sudah di export dari “Climwat” →Open → pilih data komoditi
tanaman. Maka tabel data akan terisi data yang telah dipilih.
8. Pilih “Soil”, kemudian akan muncul tabel soil
Tabel tampilan data tanah
Ikon untuk membuka data
9. Pilih open → pilih data yang sudah di export dari “Climwat” →Open → pilih data soil . Maka
tabel data akan terisi data yang dipilih
10. Pilih “CWR” akan muncul tahel hasil dari data yg input
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI 24

Tabel hasil data
11. Pilih “Schedule” untuk mengetahui secara lengkap hasil dari data yang telah di input.
Nama pengambilan lokasi ETo
Rekomendasi irigasi
12. Data dapat berupa chart dengan memilih “Chart”
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI 25

Waktu irigasi
13. Pilih “Crop Pattern”. Kemudian akan muncul table Cropping Pattern, masukkan tanggal
penanaman maka secarta otomatis akan muncul tanggal panen. Dilanjutkan dengan menginput
luasan area yang digunakan.
Tanggal panen
Tanggal tanam Data tanaman
Nama Tanaman
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI 26

14. Pilih “Scheme” maka tabel scheme supply akan muncul. Semua data akan ditampilkan secara lengkap pada tabel theme supply.
Skema yang telah jadi apabila semua data sudah dimasukkan
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI 27

ACARA 6 : AKSES INFORMASI CUACA
TUJUAN : 1.Memperoleh Informasi Cuaca Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi
2. Menafsirkan Informasi Cuaca Untuk Keperluan Praktis
LANDASAN TEORI
Informasi memegang peran yang sangat penting dalam mendukung penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi suatu bangsa. Di era globalisasi arus informasi berlangsung dan
berkembang begitu cepat melalui berbagai media, bahkan kejadian yang berasal dari berbagai
belahan dunia dapat diakses dalam waktu hampir bersamaan (real time) di berbagai tempat
belahan dunia yang lain. Arus informasi yang berkembang saat ini juga hampir merambah di
semua sektor pada berbagai tingkat lapisan masyarakat. Perkembangan arus informasi yang
begitu cepat tersebut akan sangat bermanfaat bila digunakan untuk hal-hal yang bersifat positif,
tetapi sebaliknya akan membawa petaka bila disalahgunakan untuk kegiatan yang negatif.
Salah satu bentuk penggunaan informasi cuaca yang positif adalah pemanfaatan
informasi untuk prakiraan cuaca. Melalui informasi yang cepat dan akurat tidak hanya diperoleh
prakiraan yang tepat tetapi juga bisa menyelamatkan harta benda bahkan jutaan nyawa umat
manusia. Melalui akses informasi cuaca maka dapat diprakirakan kejadian perubahan cuaca
untuk waktu tertentu di suatu wilayah dan dampak yang akan ditimbulkannya. Sebagai contoh
terjadinya berbagai macam badai yang melanda berbagai wailayah, saat ini telah mampu
diprakirakan waktu datangnya, arah pergerakannya, kecepatan serta akibat yang mungkin
ditimbulkannya. Adanya informasi tersebut memungkinkan diselamatkannya jutaan jiwa
manusia melalui kegiatan evakuasi penduduk beberapa saat sebelum peristiwa itu terjadi.
Informasi semacam itu tidak hanya dapat dimanfaatkan scara terbatas untuk kepentingan
seperti di atas, tetapi juga dapat digunakan untuk kepentingan bidang pertanian. Adanya
informasi perubahan cuaca yang dapat diakses dengan cepat, memungkinkan pengambil
kebijakan melakukan langkah-langkah yang tepat, baik untuk kepentingan bidang pertanian
dalam jangka pendek ataupun kepentingan jangka panjang. Namun keberhasilannya tidak
terlepas dari kemauan para pengambil kebijakan.
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI 28

Internet merupakan salah satu bentuk sarana akses informasi yang saat ini telah menjadi
suatu kebutuhan, terutama untuk informasi yang perlu kecepatan waktu dan bersifat global. Berbagai
negara melalui penginderaan satelit telah dapat menampilkan inofrmasi cuaca untuk kepentingan
lokal sampai kepentingan global dan dengan mudah dapat diakses melalui internet. Dengan
membuka situs-situs cuaca tertentu berbagai ragam informasi cuaca dunia dapat diperoleh mulai dari
yang berbentuk tulisa, gambar, foto, animasi, maupun video. Kemajuan teknologi saat ini sangat
penting artinya di dunia pendidikan tidak terkecuali di bidang ilmu pertanian, karena melalui
teknologi tersebut manfaat informasi cuaca dapat benar-benar dirasakan.
KEGIATAN :
1. Melalui mesin pencari (search engine) yang saudara kenal (misal Google atau Yahoo)
carilah beberapa alamat (home page) yang menginformasikan tentang cuaca. 2. Bila sudah menemukan, pahami apa saja yang diinformasikan oleh situs tersebut.
3. Ulangi kegiatan di atas (point 1 dan 2) untuk mencari situs-situs lain sampai saudara
menemukan informasi yang sesuai dengan kebutuhan saudara di bidang pertanian.
PETUNJUK PRAKTIKUM AGROMETEOROLOGI 29




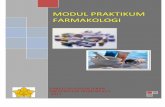

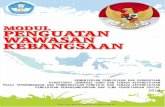


![Modul Kewirausahaan Bio-slurryhighres] Modul Kewirausahaan... · oleh Konsorsium Hivos dalam beberapa modul pelatihan sebelum “Modul Kewirausahaan Bio-slurry” ini diterbitkan.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/5e230f873e68b5019e30148d/modul-kewirausahaan-bio-slurry-highres-modul-kewirausahaan-oleh-konsorsium.jpg)











