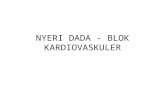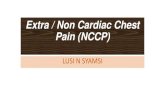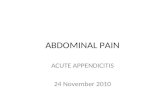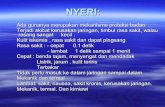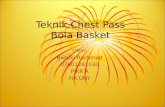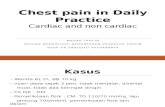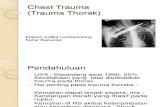Materi Kuliah Pakar Chest Pain
-
Upload
rimarahmadipta -
Category
Documents
-
view
21 -
download
0
description
Transcript of Materi Kuliah Pakar Chest Pain
PENYAKIT JANTUNG KORONER
Pendahuluan: Pembuluh darah koroner merupakan penyalur aliran darah (membawa 02 dan makanan yang dibutuhkan miokard agar dapat berfusi dengan baik. penyakit Jantung Koroner adalah salah satu akibat utama arteriosklerosis (pengerasan pembuluh darah nadi) yang dikenal sebagai atherosklerosis. Pada keadaan ini pembuluh darah nadi menyempit karena terjadi endapan-endapan lemak (atheroma dan plaques) pada didindingnya. Faktor-faktor resiko untuk terjadinya keadaan ini adalah merokok, tekanan darah tinggi, peninggian nilai kolesterol didarah, kegemukan stress, diabetes mellitus dan riwayat keluarga yang kuat untuk Penyakit Jantung Koroner. Dengan bertambahnya umur penyakit ini akan lebih sering ada. pria mempunyai resiko lebih tinggi dari pada wanita, tetapi perbedaan ini dengan meningkatnya umur akan makin lama makin kecil. Faktor-faktor resiko PJK Faktor-faktor resiko penyakit jantung koroner dikenal sejak lama berupa: 1. Hipertensi 2. Kolesterol darah 3. Merokok 4. Diet 5. Usia 6. Sex 7. Kurang latihan 8. Turunan Pada tahun 1772 Herbeden menemukan suatu sindroma gangguan pada dada berupa perayaan nyeri terlebih-lebih waktu berjalan, mendaki atau segera sesudah makan. Sebenarnya perasaan nyeri seperti ini tidak saja disebabkan oleh kelainan organ didalam toraks, akan tetapi dapat juga berasal dari otot, syaraf, tulang dan faktor psikis. Dalam kaitannya dengan jantung sindroma ini disebut Angina Pectoris,yang disebabkan oleh karena ketidak seimbangan antara kebutuhan oksigen miokard dengan penyediaannya. Penyediaan oksigen Oksigen sangat diperlukan oleh sel miokard untuk mempertahankan fungsinya, yang didapat dari sirkulasi koroner yang untuk miokard terpakai sebanyak 70-80 sehingga wajarlah apabila aliran koroner perlu ditingkatkan. Aliran darah koroner terutama terjadi sewaktu dastole padta saat otot ventrikel dalam keadaan istirahat. Banyaknya aliran koroner dipengaruhi oleh beberapa hal seperti tekanan diastolik aorta.lamanya setiap diastole dan ukuran pembuluh aretri terutama arteriole. Jadi pengurangan aliran koroner umumnya disebabkan oleh kelainan pembuluh koroner, rendahnya tekanan diastolic aorta dan meningkatnya denyut jantung.
Pemakaian Oksigen Ada beberapa hal yang dipengaruhinya yaitu : 1. Denyut jantung Apabila denyut jantung bertambah cepat maka keperluan oksigen permenit akan meningkat. 2. Kontraktilitas Dengan bekerja maka banyak dikeluarkan katekolamin (Adrenalin dan Nor Adrenalin), sehingga akan menambah tenaga kontraksi jantung. 3. Tekanan sistolik ventrikel Kiri. Makin tinggi tekanan ini, makin banyak pemakaian oksigen. 4. Ukuran jantung Jantung yang besar memerlukan oksigen yang banyak.
Etiologi: Adanya aterosklerosis koroner dimana terjadi kelainan pada intima bermula berupa bercak fibrosa (fibrous plaque) dan selanjutnya terjadi ulserasi, pendarahan, kalsifikasi dan trombosis. Perjalanan dalam kejadian aterosklerosis tidak hanya disebabkan oleh faktor tunggal, akan tetapi diberati juga banyak faktor lain seperti : hipertensi, kadar lipid, rokok, kadar gula darah yang abnormal. Angina Pectoris Adanya Angina Pectoris dapat dikenal secara: 1. Kwalitas nyeri dada yang khas yaitu perasaan dada tertekan, merasa terbakar atau susah bernafas. 2. Lokasi nyeri yaitu restrosternal yang menjalar keleher, rahang atau mastoid dan turun ke lengan kiri. 3. Faktor pencetus seperti sedang emosi, bekerja, sesudah makan atau dalam udara dingin.
Stable Angina Pectoris Kebutuhan metabolik otot jantung dan energi tak dapat dipenuhi karena terdapat stenosis menetap arteri koroner yang disebabkan oleh proses aterosklerosis. Keluhan nyeri dada timbul bila melakukan suatu pekerjaan. sesuai dengan berat ringannya pencetus dibagi atas beberapa tingkatan : 1. Selalu timbul sesudah latihan berat. 2. Timbul sesudah latihan sedang ( jalan cepat 1/2 km) 3. Timbul waktu latihan ringan (jalan 100 m) 4. Angina timbul jika gerak badan ringan (jalan biasa)
Diagnosa 1. Pemeriksaan EKG 2. Uji latihan fisik (Exercise stress testing dengan atau tanpa pemeriksaan radionuclide) 3. Angiografi koroner.
Terapi: 1. Menghilangkan faktor pemberat2. Mengurangi faktor resiko3. Sewaktu serangan dapat dipakai4. Penghambat Beta5. Antagonis kalsium6. Kombinasi
Unstable Angina Pectoris Disebabkan primer oleh kontraksi otot polos pembuluh koroner sehingga mengakibatkan iskeia miokard. patogenesis spasme tersebut hingga kini belum diketahui, kemungkinan tonus alphaadrenergik yang berlebihan (Histamin, Katekolamin Prostagglandin). Selain dari spame pembuluh koroner juga disebut peranan dari agregasi trobosit. penderita ini mengalami nyeri dada terutama waktu istirahat, sehingga terbangun pada waktu menjelang subuh. Manifestasi paling sering dari spasme pembuluh koroner ialah variant (prinzmental). Elektrokardiografi tanpa serangan nyeri dada biasanya normal saja. Pada waktu serangan didapati segmen ST elevasi. Jangan dilakukan uji latihan fisik pada penderita ini oleh karena dapat mencetuskan aritmia yang berbahaya. Dengan cara pemeriksaan teknik nuklir kita dapat melihat adanya iskemia saja ataupun sudah terjadi infark.
Terapi 1. Nitrogliserin subligual dosis tinggi. 2. Untuk frokfikaksis dapat dipakai pasta nitrogliserin, nitrat dosis tinggi ataupun antagonis kalsium. 3. Bila terdapat bersama aterosklerosis berat, maka diberikan kombinasi nitrat, antagonis kalsium dan penghambat Beta. 4. Percutanous Transluminal coronary angioplasty (PTCA) atau coronary by Pass Graff Surgery (CBGS)
SINDROM KORONER AKUT (SKA)
A. DefinisiPengertian Sindrom Koroner Akut (SKA) merujuk pada sekumpulan keluhan dan tanda klinis yang sesuai dengan iskemia miokardium akut. Sindrom koroner akut merupakan suatu spektrum dalam perjalanan penderita penyakit jantung koroner (aterosklerosis koroner). SKA dapat berupa angina pektoris tidak stabil, infark miokard dengan non-ST elevasi (NSTEMI), infark miokard dengan ST elevasi (STEMI) dan atau kematian jantung mmendadak.B. EpidemiologiSindrom koroner akut adalah kegawatan kardiovaskuler yang merupakan penyebab utama kematian. Kematian terbanyak terjadi di luar rumah sakit. Kematian yang terjadi sebelum pasien sampai di rumah sakit berhubungan dengan aritmia maligna (VT/VF). Banyak kejadian terjadi dalam empat jam pertama setelah awal serangan. Kematian di rumah sakit lebih banyak berhubungan dengan menurunnya curah jantung termasuk gagal jantung kongestif dan syok kardiogenik. Kematian berhubungan pula dengan luasnya infark miokard. Oleh karena itu, upaya membatasi luas infark akan menurunkan mortalitas.C. PatofisiologiPenyebab terjadinya SKA secara teoritis adalah akibat thrombosis koroner dan robekan plak (plaque fissure). Pada penelitian angiografi dan studi post-mortem yang dilakukan pada pasien SKA segera setelah timbulnya keluhan menunjukan lebih dari 85 % terdapat adanya oklusi thrombus pada arteri penyebab (culprit artery). Trombus yang terbentuk merupakan campuran trombus putih (white thrombus) dan thrombus merah (red thrombus). Trombosis koroner umumnya terjadi dihubungkan dengan robekan plak. Perubahan yang tiba-tiba dari angina stabil menjadi tidak stabil atau infark miokard umumnya berhubungan dengan robekan plak pada titik di mana tekanan shear stress nya tinggi dan seringkali dihubungkan dengan plak aterosklerosis yang ringan (minor). Plak yang mengalami robekan kemudian merangsang agregasi trombosit yang selanjutnya akan membentuk thrombus. Spasme arteri koroner juga berperan pening dalam patofisiologi SKA. Perubahan tonus pembuluh darah koroner melalui Nitric Oxide (NO) endogen dapat membawa variasi ambang rangsang angina di antara satu pasien dengan yang lain antara satu waktu dengan waktu yang lain. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tonus arteri yaitu hipoksiaiii, katekolamin endogen, dan zat vasoaktif (serotonin, adenosine diphospat).Pasien dengan aterosklerosis koroner bisa mengalami gejala klinis yang bervariasi tergantung dari tingkat sumbatan arteri koroner. Gejala-gejala klinis ini meliputi angina tidak stabil, non-ST-segment elevation myocardial infarction (NSTEMI), dan ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI). Beberapa hal yang mendasari patofisiologi SKA adalah sebagai berikut:A. Plak tidak stabilPenyebab utama terjadinya SKA adalah rupturnya plak yang lipid dengan cangkang yang tipis. Umumnya plak yang mengalami ruptur secara hemodinamik tidak signifikan besar lesinya. Adanya komponen sel inflamasi yang berada di bawah subendotel merupakan titik lemah dan merupakan predisposisi terjadinya ruptur plak. Kecepatan aliran darah, turbulensi, dan anatomi pembuluh darah juga memberikan kontribusi terhadap hal tersebut.B. Ruptur plakSetelah plak ruptur, sel-sel platelet dkan menutupi atau menempel pada plak yang ruptur. Ruptur akan merangsang dan mengaktifkan agregasi platelet. Fibrinogen akan menyelimuti platelet yang kemudian akan merangsang pembentukan thrombin.C. Angina tidak stabilSumbatan thrombus yang parsial akan menimbulkan gejala iskemia lebih lama dan dapat terjadi saat istirahat. Pada fase ini trobus kaya akan platelet sehingga terapi aspirin, clopidogrel, dan GP IIb/IIIa inhibator paling efektif. Pemberian trombolisis pada fase ini tidak efektif dan malah sebaliknya dapat mengakselerasi oklusi dengan melepaskan bekuan yang bberikatan dengan thrombin yang dapat mempromosi terjadinya koagulasi. Oklusi thrombus yang bersifat intermiten dapat menyebabkan nekrois miokard sehingga menimbulkan NSTEMI.D. Mikroemboli Mikroemboli dapat berasal dari thrombus distal dan bersarang di dalam mikrovaskular koroner yang menyebabkan troponin jantung meningkat (penanda adanya nekrosis di jantung). Kondisi ini merupakan risiko tinggi terjadinya infark miokardium yang lebih luas.E. Oklusif trombusJika thrombus menyumbat total pembuluh darah koroner dalam waktu yang lama, maka akan menyebabkan STEMI. Bekuan ini kaya akan thrombin, oleh karena itu, pemberian fibrinolisis yang cepat dan tepat atau langsung dilakukan PCI dapat membatasi perluasan infark miokardium.
D. Diagnosis SKADiagnosis SKA bedasarkan keluhan khas angina umumnya. Terkadang paisen pasien tidak ada keluhan angina namun sesak nafas atau tidak khas seperti nyeri epigastrik atau sinkope yang disebut angina aquivalen. Hal ini diikuti perubahan elektrokardiogram (EKG) dan atau perubahan enzim jantung awal tidak bisa menyingkirkan adanya SKA, oleh karena perubahan EKG dan enzim baru dapat terjadi setelah beberapa jam kemudian. Pada kondisi ini diperlukan pengamatan secara serial sebelum menyingkirkan diagnosis SKA.GejalaGejala-gejala umum iskemia dan infark miokardium adalah nyeri dada retrosternal. Pasien sering kali merasa dada ditekan tau dihimpit lebih dominan dibanding rasa nyeri. Yang perlu diperhatikan dalam evalusi keluhan nyeri dada iskemik SKA adalah:1. Lokasi nyeri; di daerah retrosternal dan pasien sulit melokalisir rasa nyeri2. Deskripsi nyeri; pasien mengeluh rasa berat seperti dihimpit, ditekan atau diremas, rasa tersebut lebih dominan dibandingkan rasa nyeri. Perlu di waspadai juga bila pasien mengeluh nyeri epigastrik, sinkope atau sesak nafas (angina ekuvalen)3. Penjalaran nyeri; penjalaran ke lengan kiri, bahu, punggung , leher rasa terceklik atau rahang bawah (rasa ngilu) kadang penjalaran ke lengan kanan atau kedua lengan.4. Lama nyeri; nyeri pada SKA lebih dari 20 menit5. Gejala sitemik; disertai keluhan seperti mual, muntah atau kkeringat dingin.Hal-hal dapat menyerupai nyeri dada iskemia: Emboli paru akut Efusi pericardial akut dengan tamponade jantung Tension pneumothorax Pericarditis GERD (Gastro Esophageal reflux Disease)Pemeriksaan FisikPemeriksaan fisik dilakukan untuk menegakna diagnosis, menyingkirkan kemungkinan penyebab nyeri dada lainya dan mengevaluasi adanya komplikasi SKA. Pemeriksaan fisik pada SKA umumnya normal. Terkadang pasien terlihat cemas, keringat dingin atau didapat tandankomplikasi berupa takipnoe, takikardia, adanya gallop S3, ronki basah halus di paru, atau terdengar bising jantung (murmur). Bila tidak ada komplikasi hampir tidak ditemukan kelainan yang berarti.ElektrokardiogramPemeriksaan EKG merupakan pemeriksaan penunjang penting dalam diagnosis SKA untuk menentukan tata laksana selanjunya. Berdasarkan gambaran EKG pasien SKA dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok:1. Elivasi segmen ST atau LBBB (left bundle branch block yang dianggap baru.Didapatkan gambaran elevasi segmen ST mminimal di dua lead yang berhubungan.2. Depresi segment ST atau inversi gelombang T yang dinamis pada saat pasien mengeluh nyeri dada.3. EKG non diagnostik baik normal ataupun hanya ada perubahan minimal.LaboratoriumPemeriksaan laboratorium untuk menilai adanya tanda nekrois miokardium seperti CK-MB, Troponin T dan I, serta Mioglobin dipakai untuk menegakan diagnosis SKA. Troponin lebih dipilih karena lebih sensitif daripada CKMB. Troponin juga berguna untuk diagnosis, stratifikasi risiko, dan menentukan prognosis. Troponin yang meningkat dihubungkan dengan peningkatan risiko kematian. Pada pasien dengan STEMI, reperfusi tidak boleh ditunda hanya untuk menunggu enzim jantung.Mioglobin merupakan suatu protein yang dilepaskan dari sel miokardium yang mengalami kerusakan, dapat meningkat setelah jam-jam awal terjadinya infark dan mencapai puncak pada jam 1 s/d ke 4 dan tetap tinggi sampai 24 jam.CKMB merupakan isoenzim dari creatinin kinase, yang merupakan kosentrasi terbesar dari miokardium. Dalam jumlah kecil CKMB juga dapat dijumpai di otot rangka, usus kecil atau diapragma. Mulai meningkat 3 jam setelah infark dan mencapai puncak 12-14 jam. CKMB akan mulai menghilang dalam darah 48-72 jam setelah infark.Troponin mengatur interaksi kerja aktin dan myosin dalam otot jantung dan lebih spesifik dari CK-MB. Mempunyai dua bentuk Troponin T dan I. Enzi mini mulai meningkat pada jam 3 s/d 12 jam setelah onset iskemik. Mencapai puncak pada 12-24 jam dan masih tetap tinggi sampai hari ke 8-21 (TropT) dan 7-14 (Trop I). peningkatan enzim ini berhubungan dengan bukti adanya nekrosis miokard dan menunjukan prognosis yang buruk pada SKA.
E. KomplikasiSindroma koroner akut dapat menyebabkan berbagai komplikasi. Komplikasi yan paling sering adalah gangguan irama dan gangguan pompa jantung. Gangguan irama dapat bersifat fatal bila menyebabkan henti jantung, misalnya pada VF atau VT tanpa nadi. Komplikasi gagal jantung pada ACS STEMI di klasifikasikan dalam Klasifikasi Kilip. Berikut ini klasisikasi Kilip dan kaitan dengan Mortalitas di RS Klas Killip
Mortalitas RS(%)
I. Tidak ada komplikasiII. HF ringan, ronchi, S3, tanda bendungan paru.III. Edema ParuIV. Shock Kardiogenik617
3881
F. Tata LaksanaSecara umum tatalaksana STEMI dan NSTEMI hampir sama baik pre maupun hospital hanya berbeda dalam strategi reperfusi terapi, dimana STEMI lebih ditekankan untuk segera melakukan reperfusi baik dengan medikamentosa (trombolisis) atau intervensi (Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendation(AHA/ACC) tahun 2010, sangat ditekankan waktu efektif reperfusi terapi. Bila memungkinkan trombolisis dilakukan saat prehospital untuk menghemat waktu.Tatalaksana SKA dibagi atas: Pra Rumah Sakit (Prehospital) Rumah Sakit (Hospital)PREHOSPITAL Monitoring, dan amankan ABC. Persiapkan RJP dan defibrilasi Berikan aspirin, dan pertimbangkan oksigen, nitrogliserin, dan morfin jika diperlukan. Pemeriksaan EKG 12-sadapan dan interpretasi Lakukan pemberitahuan ke RS untuk melakukan persiapan penerimaan pasien dengan STEMI Bila akan diberikan fibrinolitik prehospital, lakukan check-list terapi fibrinolitik.HOSPITALRuang gawat daruratPenilaian awal di IGD (175 mmHg)Kontraindiksi absolute terapi fibrinolitik adalah: Perdarahan intrakanial kapanpun Stroke iskemik kurang dari 3 bulan dan lebih dari 3 jam Kecurigaan duseksi aorta Tumor intracranial Adanya kelainan struktur vascular serebral (AVM) Perdarahan internal aktif atau gangguan sistem pembekuan darah Cedera kepala tertutup atau cedera wajah dalam 3 bulan terakhirKontraindikasi relatif terapi fibrinolitik adalah: Tekanan darah yang tidak terkontrol TD sistolik>180 mmHg, TD diastolic>110mmHg Riwayat stroke iskemik>3bulan, demensia Trauma atau RJP lama (>10 menit) atau operasi besar3 jam Tersedia ahli PCI Kontak medic-balloon atau door-balloon