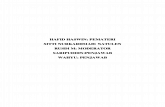MAKALAH PANCASILA
Transcript of MAKALAH PANCASILA

BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian dan Definisi HAM
Hak Asasi Manusia atau sering kita sebut sebagai HAM adalah terjemahan dari istilah Human Rights atau The Right of Human. Secara terminologi istilah ini artinya adalah Hak-Hak Manusia. Namun dalam beberapa literatur, pemakaian istilah Hak Asasi Manusia (HAM) lebih sering digunakan dari pada pemakaian Hak-hak Manusia. Di Indonesia hak-hak manusia pada umumnya lebih dikenal dengan istilah “hak asasi” sebagai terjemahan dari basic rights (Inggris) dan grondrechten (Belanda), atau bisa juga disebut hak-hak fundamental (civil rights).
Istilah hak-hak asasi secara monumental lahir sejak keberhasilan Revolusi Perancis tahun 1789 dalam “Declaration des Droits de L’homme et du Citoyen” (hak-hak asasi manusia dan warga negara Perancis), dengan semboyan Liberte, Egalite, Fraternite. Istilah HAM berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman dalam arti perubahan peradaban manusia dari masa ke masa. Pada mulanya dikenal dengan sebutan natural rights (hak-hak alam), yang berpedoman kepada teori hukum alam bahwa; segala sesuatu berasal dari alam termasuk HAM. Istilah ini kemudian diganti dengan The Rights of Man, tetapi akhirnya tidak diterima, karena tidaak mewakili hak-hak wanita. Setelah Perang Dunia II dan terbentuknya PBB, maka muncul istilah baru yang lebih populer sekarang yaitu Human Rights yang di Amerika Serikat dikenal dengan sebutan Civil Rights. Perancis menyebutnya: Droit de L’ Homme; Belanda: Menselijke Rechten. Namun dibalik beragamnya sebutan untuk Hak Asasi Manusia, secara pengertian masih memiliki makna yang sama. Yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Martabat manusia sebagai substansi sentral hak-hak manusia mengandung aspek bahwa manusia memiliki hubungan secara eksistensial dengan Tuhannya. Karena itu pada dasarnya, setiap manusia memiliki martabat yang sama. Dengan demikian, ide dasar hak-hak asasi manusia pada dasarnya diletakkan pada sebuah pandangan bahwa manusia (lengkap dengan potensi hak asasi yang melekat pada dirinya) harus diakui dan diperlakukan dalam posisi sederajat dan kedudukan yang sama.

2.2 HAM menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 dan Tap MPR No. XVII /MPR/1998
2.2.1 HAM menurut UU Nomor 39 Tahun 1999
Secara garis besar, HAM menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 terdiri dari :1. Hak untuk hidup2. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan3. Hak mengembangkan diri4. Hak memperoleh keadilan5. Hak atas kebebasan pribadi6. Hak atas rasa aman7. Hak atas kesejahteraan8. Hak turut serta dalam pemerintahn9. Hak wanita10. Hak anak
2.2.2 HAM menurut Tap MPR No. XVII/MPR/1998Secara garis besar, HAM menurut Tap MPR No. XVII/MPR/1998 terdiri dari :
11. Hak untuk hidup12. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan13. Hak mengembangkan diri14. Hak keadilan15. Hak kemerdekaan16. Hak atas kebebasan informasi17. Hak keamanan18. Hak kesejahteraan
2.3 HAM menurut UUD 1945
2.3.1 Pembukaan UUD 1945
a) Alinea I : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah haak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.
b) Alinea IV : “… Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial……”

2.3.2 Batang Tubuh UUD 1945
Secara garis besar hak-hak asasi manusia tercantum dalam pasal 27 sampai 34 dapat dikelompokkan menjadi :a) Hak dalam bidang politik (pasal 27 ayat 1 dan pasal 28),b) Hak dalam bidang ekonomi (pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan 34),c) Hak dalam bidang sosial budaya (pasal 29, 31 dan 32),d) Hak dalam bidang hankam (pasal 27 ayat 3 dan pasal 30).Berdasarkan amandemen UUD 1945, hak asasi manusia tercantum dalam Bab X A Pasal 28 A sampai dengan 28 J.
2.4 Negara Hukum
2.4.1 Konsep Negara Hukum
Istilah negara hukum ada yang menyebutnya dengan Rechsstaat dan ada pula disebut dengan Rule of Law. Sarjana Eropa Kontinental menyebutnya dengan Rechsstaat. Sarjana Hukum Anglo Saxon (Inggeris dan Amerika) menyebutkan negara hukum dengan Rule of Law.
Perumusan ciri-ciri Negara Hukum yang dilakukan oleh F.J. Stahl, yang kemudian ditinjau ulang oleh International Commision of Jurist pada Konferensi yang diselenggarakan di Bangkok tahun 1965, yang memberikan ciri-ciri sebagai berikut:
1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
2. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak;3. Pemilihan Umum yang bebas;4. Kebebasan menyatakan pendapat;5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi;6. Pendidikan Kewarganegaraan.
Seperti dijelaskan di atas, jelaslah bahwa sebuah Negara Hukum haruslah memiliki ciri atau syarat mutlak bahwa negara itu melindungi dan menjamin Hak Asasi Manusia setiap warganya. Dengan demikian jelas sudah keterkaitan antara Negara hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana Negara Hukum wajib menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia setiap warganya.

2.4.2 Hubungan Negara Hukum dan HAM
Pada tahun 1966 di Jakarta diadakan Seminar Nasional Indonesia tentang Indonesia sebagai Negara Hukum. Yang mana salah satu hasilnya adalah dirumuskannya prinsip-prinsip negara hukum. Prinsip-prinsip itu adalah:
1. Prinsip-prinsip jaminan dan perlindungan terhadap HAM;
2. Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak.
Artinya Indonesia sebagai Negara Hukum amatlah menghormati prinsip – prinsip penegakan HAM. Dilihat dari segi hukum dan konstitusi, tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan HAM tercermin dari berbagai ketentuan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45) dan Pancasila, dalam Undang-undang Dasar yang telah di amandemen, Undang-undang Nomor 39/1999 tentang HAM, Undang-undang Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM.
Ratifikasi yang telah dilakukan terhadap sejumlah instrumen HAM intemasional:
1. Dalam Pembukaan UUD 45 dengan tegas dinyatakan bahwa “pejajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.
2. Dalam amandemen kedua UUD 1945, pasal 28 telah dirubah menjadi bab tersendiri yang memuat 10 pasal mengenai Hak Asasi Manusia.
3. Dalam Undang-undang Nomor 39/1999 tentang HAM telah dimuat hak asasi manusia yang tercantum dalam instrumen utama HAM internasional, yaitu : Deklarasi Universal HAM, Konvensi hak sipil dan politik, Konvensi hak ekonomi, sosial dan budaya, konvensi hak perempuan, konvensi hak anak dan konvensi anti penyiksaan. Undang-undang ini selain memuat mengenai HAM dan kebebasan dasar manusia, juga berisi bab-bab mengenai kewajiban dasar manusia, Komnas HAM, partisipasi masyarakat dan pengadilan HAM.
4. Dalam Undang-undang Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM khususnya dalam Bab III dinyatakan bahwa Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat.
5. Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah konvensi HAM internasional, di antaranya yang terpenting adalah:
Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), diratifikasi dengan UU No.7 /1984.
Konvensi HAK Anak (CRC), diratifikasi dengan Keppres No.36/1990. Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), diratifikasi dengan UU No.5/1998. Konvensi Penghapusan Diskriminasi Ras (CERD), diratifikasi dengan UU
No.29/1999.10. Sejumlah (14) konvensi ILO (Hak pekerja).

Pembentukan konstitusi ini merupakan bentuk tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu pembentukannya juga mengandung suatu misi mengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh PBB sebagai Negara Hukum, serta yang terdapat dalam berbagai instrument hukum lainnya yang mengatur hak asasi manusia yang telah disahkan dan atau diterima negara Republik Indonesia.