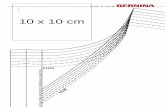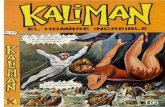lopo04-26
-
Upload
arhami-arief -
Category
Documents
-
view
17 -
download
0
description
Transcript of lopo04-26

Lokakarya Nasional Sapi Potong 2004
167
PROSPEK PENGEMBANGAN USAHA SAPI POTONG DALAM MENDUKUNG AGRIBISNIS YANG BERDAYA
SAING DI NUSA TENGGARA TIMUR
(Prospect of Beef Cattle Development to Support Competitiveness Agribusiness in East Nusa Tenggara)
J. NULIK, YUSUF dan H. MARAWALI
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Nusa Tenggara Timur
ABSTRACT
East Nusa Tenggara is an archipelagical province having three large islands (Flores, Sumba and Timor) mostly consisted of marginal lands with livestock, especially cattle, as an important income source. Livestock population in 1998 consisted of cattle 611,855 heads, buffalo 177,655 heads, and horse 185,347 heads. The population in 2003 decreased down to: 512,999 cattle, 134,900 buffalo and 94,625 horses, owing to: (1) inter-islands of cattle be low standard weight and uncontrolled, (2) high sloughing of productive cows, (3) lack in breeding and livestock management. Thus improvements should be concentrated on: (1) forage development feeding management, (2) breeding inpraventherts, (3) improvements in human researches and institutions, and (4) improvement in support facilities.
Key words: Beef cattle, development of agribusiness, dry land
ABSTRAK
Propinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah kepulauan dengan tiga pulau besar (Flores, Sumba dan Timor) yang sebagian besar wilayah merupakan lahan marginal dengan usaha peternakan terutama ternak sapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pertanian rakyat dan berperan penting sebagai sumber pendapatan. Populasi ternak besar pada tahun 1998 terdiri dari sapi sebanyak 611.855 ekor, kerbau 177.655 ekor, dan kuda 185.347 ekor. Populasi tersebut pada tahun 2003 mengalami penurunan yang tajam menjadi sapi sebanyak 512.999 ekor, kerbau 134.900 ekor, dan kuda 94.625 ekor, diduga karena: (1) pengeluaran ternak antar pulau yang tidak memenuhi standar bobot badan dan tidak terkendali; (2) pemotongan betina produktif yang cukup tinggi; (3) belum optimalnya breeding ternak; serta (4) sistem pemeliharaan yang ekstensif tradisonal. Oleh karena itu arah kebijakan pengembangan ternak mendukung uasaha agribisnis sapi dapat diwujudkan dengan melakukan beberapa program pengembangan yang meliputi: (1) pengembangan hijauan makanan ternak dan penyediaan pakan baik dalam bentuk segar maupun pakan awet; (2) Pembibitan ternak; (3) pengembangan SDM dan kelembagaan; dan (4) pengembangan sarana dan prasarana peternakan.
Kata kunci: Sapi potong, pengembangan agribisnis, lahan kering
PENDAHULUAN
Latar belakang
Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan propinsi dengan 566 pulau yang di antaranya terdapat tiga pulau besar yaitu Flores, Sumba dan Timor. NTT memiliki iklim yang paling kering di Indonesia dengan musim kemarau yang berlangsung panjang antara 8−9 bulan per tahun dan jumlah curah hujan kurang
dari 1500 mm/tahun selama musim hujan. Akibat musim kemarau yang panjang terdapat banyak lahan marginal yang hanya cocok untuk tanaman semusim dan tahunan dengan rataan produksi yang relatif rendah. Oleh karena itu di daerah ini peternakan berperan penting sebagai sumber pendapatan petani terutama dalam mengantisipasi kegagalan panen tanaman pangan.
Pemeliharaan ternak sapi di NTT baru mulai dikenal pada awal abad ke-20, ketika

Lokakarya Nasional Sapi Potong 2004
168
bersamaan dimasukkan dua jenis sapi yaitu, sapi Bali ke pulau Timor dan sapi Ongole ke Pulau Sumba yang kemudian dikenal sebagai sapi Sumba Ongole. Sampai tahun 1980-an populasi sapi berkembang dengan cepat. Data tahun 1998 menunjukkan populasi ternak sapi potong di NTT berjumlah lebih dari 700.000 ekor (ANONYM, 1998) sehingga NTT dikenal sebagai salah satu daerah pemasok sapi potong dan bibit bagi daerah lainnya di Indonesia. Sebesar 85% dari jumlah tersebut terdapat di Pulau Timor (ANONYM, 1993) yang didominasi oleh sapi Bali.
Apabila dicermati secara mendalam, perkembangan sapi Bali di Timor jauh lebih cepat dibanding perkembangan sapi Ongole di Sumba. Populasi ternak sapi Ongole menurut data terakhir hanya sekitar 50.000 ekor, sedangkan sapi Bali di Timor telah melebihi 600.000 ekor. Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya perkembangan sapi Ongole ini telah didokumentasikan, antara lain: (i) rendahnya angka reproduksi; (ii) manajemen yang masih tradisional, penyakit dan lain-lain. Di lain pihak Pulau Sumba dinilai mempunyai potensi yang memadai untuk pengembangan ternak, terutama karena ketersediaan padang penggembalaan yang masih cukup luas, dan masih memungkinkan untuk menampung ternak sapi minimal dua kali lipat jumlah yang ada sekarang ini.
Pada tahun 1914, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Pulau Sumba sebagai pusat pembibitan sapi Ongole murni. Kebijakan ini dipertegas lagi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 bahwa Pulau Sumba merupakan satu-satunya daerah di Indonesia sebagai pusat pembibitan sapi Ongole murni.
Dalam rangka mempercepat peningkatan populasi dan produktivitas sapi potong dilakukan penyegaran darah (genetik baru) melalui impor sapi bibit. Adanya import sapi Brahman dari Australia oleh Pemerintah Pusat dalam beberapa tahap yaitu tahun 1975, 1979, 1981, 1982, 1996 (DINAS PETERNAKAN SUMBA TIMUR, 1989) dan tahun 2001 sebanyak 650 ekor (KONFIRMASI PRIBADI DENGAN DINAS PETERNAKAN SUMBA TIMUR, 2003) merupakan kebijakan yang bertujuan untuk percepatan peningkatan populasi ternak sapi di Pulau Sumba. Namun tidak tersedianya data perkembangan populasi maupun manajemen
ternak tersebut, mungkin disebabkan karena lemahnya fungsi monitoring dan evalauasi setelah ternak berada ditangan penggaduh (masyarakat). Sehingga sulit memperoleh informasi yang jelas tentang kemajuan ataupun kegagalan yang dicapai.
Tujuan dan sasaran
Tujuan dan sasaran penulisan makalah ini adalah: (1) Menghimpun data dan informasi tentang usaha ternak sapi di NTT, (2) Menganalisis tentang potensi dan prospek pengembangan agribisnis usaha ternak sapi, (3) Merumuskan program kebijakan untuk mendukung pengembangan usaha ternak sapi, dan (4) Membangun komunikasi jaringan kerja penelitian dan pengembangan usaha ternak sapi dengan berbagai stakeholders.
POTENSI DAN PROSPEK PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
PETERNAKAN DI NUSA TENGGARA TIMUR
Potensi pengembangan
Konsumsi perkapita dari produk peternakan diharapkan akan sejalan dengan perbaikan tingkat pendapatan dan kemampuan tingkat penyediaan produk disamping peningkatan kesadaran gizi konsumen. KASRYNO (1997) menyatakan bahwa secara historis konsumsi perkapita produksi daging, telur dan susu dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan yang nyata bahkan untuk beberapa komoditas, seperti daging unggas dan telur, telah mampu memenuhi target. Namun demikian, terlepas dari adanya perbaikan pendapatan masyarakat dan meningkatnya kemampuan bidang usaha untuk menyediakan produk ternak yang lebih berkualitas.
Potensi sumberdaya alam di NTT berbeda dengan tipe iklim di sebagian besar wilayah di Indonesia. Hal ini terlihat dari fluktuasi curah hujan bulanan sangat besar dari tahun ketahun yang merupakan salah satu kendala dalam pembangunan pertanian, tetapi masih potensial untuk pengembangan subsektor peternakan.
Lahan perlu mendapat perhatian dilihat dari kesuburannya, dibagi dalam dua bagian, yaitu pulau-pulau yang termasuk ke dalam “busur

Lokakarya Nasional Sapi Potong 2004
169
dalam” seperti Pulau Flores, Alor dan beberapa pulau kecil lainnya dan pulau-pulau “busur luar“ yang terdiri atas Pulau Sumba, Pulau Rote, Pulau Sawu dan Pulau Timor. DIWYANTO dan PRAWIRADIPUTRA (1995) menyatakan bahwa tanah di wilayah yang termasuk busur dalam pada umumnya lebih subur daripada kelompok pulau-pulau yang termasuk busur luar. Daerah-daerah pertanian dijumpai di dataran aluvial dan lereng-lereng gunung berapi. Sedangkan pulau-pulau yang termasuk busur luar tidak terdapat gunung berapi tanahnya tidak subur dengan kadar bahan organik yang rendah. BAMUALIM dan SALEH (1992) menyatakan bahwa hasil analisis hijauan yang berasal dari padang penggembalaan alam di kepulauan busur dalam jauh lebih baik daripada yang terdapat di pulau Sumba dan Timor.
Luas dan sistem penggunaan lahan di NTT bervariasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Perkiraan luas areal, jumlah ternak dan daya tampung disajikan dalam Tabel 1. NULIK dan BAMUALIM (1998) menyatakan bahwa dengan cara mengkonversi sejumlah ternak herbivora (sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba) dalam satu unit ternak (UT) maka dapat diperkirakan daya dukung lahan yang terdapat di beberapa tempat di NTT.
Luas lahan pengembalaan dari Tabel 1, diperkirakan telah termasuk lahan yang sebenarnya digunakan untuk keperluan lainnya seperti lahan kehutanan dan perkebunan. Data tersebut di atas memperlihatkan bahwa NTT pada umumnya dan khususnya Pulau Sumba dan Pulau Timor serta Pulau Flores masih memiliki potensi lahan penggembalaan yang cukup luas untuk pengembangan produksi ternak. Tingginya populasi ternak dan luasnya areal padang rumput di NTT merupakan potensi yang sangat besar untuk berdayakan.
Laju pertumbuhan dan produksi ternak di NTT
Peternakan rakyat merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pertanian rakyat NTT. Distribusi ternak antara ke tiga pulau besar (Timor, Sumba dan Flores) tidak merata, sangat mungkin berhubungan dengan jumlah penduduk.
Populasi ternak selama kurun waktu Pelita III dan IV (1987-1988) terus meningkat dengan kenaikan rata-rata per tahun sebagai berikut: sapi 5,18%, kerbau 4,30%, kuda 0,46%, kambing 5,93%, domba 6,80%, babi 6,58% dan unggas 6,92%. Pada tahun 1988 populasi sapi sebanyak 611.855 ekor, kerbau 177.655 ekor, kuda 185.347 ekor, kambing 414.377 ekor, domba 89.427 ekor, babi 1.056.163 ekor dan unggas 4.989.910 ekor (PELLOKILA et al., 1991). Populasi dan penyebaran ternak tersebut erat hubungannya dengan tersedianya lahan untuk penggembalaan, kegiatan pertanian dan penyebaran penduduk. Selain itu populasi dan penyebaran ternak mempunyai hubungan dengan iklim dan daya adaptasi dari ternak yang bersangkutan. Sedangkan populasi ternak dari tahun (1994-2003) menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat untuk beberapa jenis ternak dengan tingkat kenaikan yang berbeda, kecuali untuk ternak sapi dan unggas (Tabel 2).
Kenaikan populasi sampai tahun 1998 adalah kerbau 1,50%, kuda 0,93%, kambing 2,90%, domba 3,10%, babi 2,40% sedangkan ternak lainnya perkembangan populasi menurun tajam. Selanjutnya perkembangan populasi semua jenis ternak dari tahun 1998 hingga tahun 2003 mengalami penurunan yang tajam (Tabel 1). Diduga karena: (1) pengeluaran ternak antar pulau yang tidak memenuhi standar bobot badan dan tidak
Tabel 1. Perkiraan luas areal dan daya tampung ternak di NTT
Lokasi (ha) Luas areal (ha) Padang rumput (ha) Unit ternak (UT) Daya dukung (ha/UT)
Pulau Sumba 1.085.440 770.600 145.960 5,3 Pulau Flores 1.909.500 406.170 129.630 3,1 Pulau Timor 1.699.060 705.040 537.110 1,3 NTT 4.694.000 1.475.680 812.700 1,8
Sumber: NULIK dan BAMUALIM (1998)

Lokakarya Nasional Sapi Potong 2004
170
Tabel 2. Populasi ternak di Nusa Tenggara Timur tahun 1994-2003
Jumlah ternak (ekor) Tahun
Sapi Kerbau Kuda Kambing Domba Babi
1994 786.295 164.828 162.578 599.976 108.356 1.406.072 1995 785.115 191.125 170.575 612.229 111.498 1.537.982 1996 782.467 157.530 146.614 601.126 138.046 2.034.336 1997 792.461 159.893 148.729 618.529 142.335 2.181.341 1998 725.704 162.291 150.112 636.466 146.747 2.233.693 1999 726.439 164.726 151.508 654.922 151.296 2.287.302 2000 486.323 125.797 83.856 377.463 48.745 731.959 2001 495.052 126.574 87.634 398.560 52.074 953.457 2002 503.155 132.497 93.156 420.836 55.631 1.170.473 2003 512.999 134.900 94.625 435.151 56.403 1.225.040
Sumber: PUSAT DATA PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) (2002) dan STATISTIK PETERNAKAN (2002; 2003)
terkendali, (2) pemotongan betina produktif yang cukup tinggi, (3) belum optimalnya breeding ternak, serta sistem pemelihraan yang ekstensif tradisonal.
Pemotongan ternak
Penyediaan konsumsi daging di NTT berasal dari ternak yang dipotong baik pemotongan resmi di Rumah Potong Hewan (RPH) maupun pemotongan di luar RPH yang dilaporkan melalui petugas di masing-masing kecamatan.
Tabel 3 terlihat bahwa pada tahun 2001, ternak kambing/domba merupakan ternak terbanyak yang dipotong yaitu sebanyak 456.817 ekor diikuti ternak babi 405.219 ekor, sapi 27.228 ekor dan kerbau 3.480 ekor. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, urutan banyaknya ternak yang dipotong mempunyai pola yang hampir sama yaitu ternak yang dipotong paling banyak adalah kambing disusul babi, sapi dan terakhir kerbau. Jumlah ternak kambing yang dipotong naik dari 204.237 ekor menjadi 456.817 ekor, babi naik dari 90.698 ekor menjadi 405.219 ekor, kerbau naik dari 3.791 ekor menjadi 3.480 ekor dan sapi naik dari 25.888 ekor menjadi 27.228 ekor. Meningkatnya pemotongan seluruh ternak besar dan sedang kecuali Babi, diduga karena meningkatnya permintaan konsumsi
daging. Hal ini disebabkan adanya kesadaran gizi masyarakat dan meningkatnya pendapatan penduduk.
Rasio ternak besar yang dipotong terhadap populasi ternak tersebut pada tahun 2001 adalah sapi 5,50%; kerbau 2,74% kambing 10,37% dan babi 42,50%. Sedangkan pada tahun 2000 ratio untuk jenis ternak sapi 5,32%, kerbau 2,62%, kambing 47,92% dan babi 12,39%. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa walaupun telah terjadi kenaikan populasi ternak besar tahun 2001 dibandingkan tahun sebelumnya, namun jumlah ternak yang dipotong selalu meningkat. Dengan demikian secara absolut kenaikan ternak hanya untuk memenuhi yang dipotong pada periode yang sama.
Perkembangan pemotongan ternak dari tahun 1995 hingga 2003 mengalami peningkatan kecuali ternak kambing dan babi pada tahun 2000 dan 2001 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2000 terjadi penurunan namun kemudian meningkat kembali (Tabel 4).
Pola perdagangan
Perdagangan ternak di NTT didominasi oleh perdagangan ternak hidup dari wilayah sentra produksi ke konsumen akhir. Ternak hidup diangkut langsung dari pasar-pasar

Lokakarya Nasional Sapi Potong 2004
171
Tabel 3. Banyaknya ternak yang dipotong di Nusa Tenggara Timur tahun 2000-2001
2000 2001 Jenis ternak
Dalam RPH Luar RPH Jumlah Dalam RPH Luar RPH Jumlah
Sapi 24.316 1.572 25.888 24.753 2.475 27.228 Kerbau 3.145 146 3.291 3.164 316 3.480 Kambing/domba 34.974 169.263 204.237 36.988 419.829 456.817 Babi 62.217 28.481 90.698 81.044 324.175 405.219 NTT 124.652 199.462 324.114 145.949 746.795 892.744
Sumber: DINAS PETERNAKAN PROPINSI NTT (2001)
Tabel 4. Pemotongan ternak di Nusa Tenggara Timur tahun 1995-2003
Jumlah ternak (ekor) Tahun
Sapi Kerbau Kuda Kambing Domba Babi
1995 21.198 1.911 853 153.057 11.150 307.596 1996 22.692 2.363 733 150.282 13.805 406.867 1997 23.774 2.398 818 154.632 14.234 436.268 1998 13.848 2.434 826 159.117 14.675 446.739 1999 25.425 3.295 909 163.731 15.130 457.460 2000 26.261 3.459 922 120.788 19.108 308.319 2001 27.228 3.481 964 127.539 20.413 405.219 2002 30.692 4.372 2.049 134.668 - - 2003 31.293 4.856 2.082 139.249 20.305 490.016
Sumber: PUSAT DATA PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA), DINAS PETERNAKAN PROPINSI NTT (2002), STATISTIK PETERNAKAN (2002; 2003)
ternak di wilayah produsen ke rumah potong hewan (RPH) di daerah konsumen. Konsumen utama ternak dari NTT adalah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Transportasi sapi keluar dari NTT dilakukan melalui laut ke Surabaya, kemudian diangkut melalui darat ke tujuan akhir seperti Jakarta dan Bogor.
Struktur perdagangan ternak relatif sederhana, melibatkan petani, pedagang perantara, eksportir (regional), jagal dan konsumen akhir. Struktur perdagangan tersebut digambarkan secara umum pada Gambar 1 (RANTETANA dan NAPITUPULU, 1991; YUSUF et al., 2002).
Dari semua pelaku pasar yang terlihat dalam saluran pemasaran ternak, petani mempunyai posisi yang paling lemah. Hal ini karena petani pada umumnya tidak mempunyai akses terhadap informasi pasar yang berlaku yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan
tawar menawar, sementara pihak eksportir secara saksama mengikuti perkembangan harga yang terjadi di tingkat konsumen. Disamping itu penentuan berat badan ternak yang berdasarkan perkiraan/taksiran juga menyebabkan petani berada pada posisi yang lemah (YUSUF et al., 2002).
Angka pengeluaran ternak dari NTT terlihat pada (Tabel 5). Pengeluaran ternak tersebut adalah dengan tujuan Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta untuk jenis ternak sapi dan kerbau.
Harga perdagangan ternak besar di pasaran seperti sapi, kerbau, dan kuda menunjukkan kecenderungan terus meningkat (Tabel 6). Lonjakan harga terjadi pada tahun 1995. Rata-rata harga perdagangan sapi di pasaran per ekor pada tahun 1994 hanya sebesar Rp 371.800, kemudian melonjak menjadi Rp 804.300 pada tahun 1995. Tingkat harga

Lokakarya Nasional Sapi Potong 2004
172
tersebut terus meningkat hingga akhirnya menjadi sekitar Rp 1.800.000 per ekor pada tahun 2000. Sementara itu rata-rata harga perdagangan kerbau di pasaran pada tahun 1994 adalah Rp 483.900 per ekor, dan naik menjadi Rp 755.600 pada tahun 1995. Peningkatan harga kerbau terus berlangsung hingga akhirnya mencapai Rp 1.150.000 per ekor pada tahun 1999.
Harga ternak kecil seperti ternak babi pada tahun 1994 di pasaran sebesar Rp 90.700,
tetapi telah menjadi Rp 516.100 pada tahun 2000. Untuk ternak kambing juga menunjuk-kan kecenderungan yang sama. Rata-rata harga kambing di pasaran pada tahun 1994 baru Rp 44.300 per ekor, tetapi pada tahun 1999 telah menjadi Rp 135.200. Sementara harga ternak kambing di tingkat produsen juga mengalami perubahan yang cukup besar pada tahun 2001. Rata-rata harga pada tingkat produsen untuk semua jenis ternak mengalami kenaikan, namun harga ini jauh dibawah harga di pasaran.
Gambar 1. Struktur perdagangan sapi potong di NTT
Tabel 5. Pengeluaran ternak dari Nusa Tenggara Timur Tahun 1995-2001
Jumlah ternak (ekor) Tahun Sapi Kerbau Kuda Kambing Domba Babi
1994 70.905 12.841 7.509 203 - - 1995 58.735 13.268 6.445 30 15 5.647 1996 54.835 9.897 5.946 193 7 8.265 1997 49.990 7.371 6.146 100 10 1.091 1998 119.699 22.242 7.295 365 8 2.411 1999 65.005 10.985 5.715 - - - 2000 52.022 13.896 5.716 - - - 2001 55.680 9.528 4.588 - - - 2002 42.410 6.319 2.670 - - - 2003 35.061 3.566 2.868 - - -
Sumber: PUSAT DATA PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA), DINAS PETERNAKAN PROPINSI NTT (2002) dan STATISTIK PETERNAKAN (2002; 2003)
Pedagang perantara
RPH/jagal lokal
Konsumsi lokal
Petani produksi
Pasar ternak
Penggemukan
Eksportir regional
RPH/jagal
Konsumen ekstenal

Lokakarya Nasional Sapi Potong 2004
173
Tabel 6. Rata-rata harga beberapa komoditas peternakan di Nusa TenggaraTimur tahun 1995-2001
Ternak 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Perdagangan besar
Sapi 804.253 883.572 974.743 1.113.279 1.515.405 1.848.080 -
Kerbau 755.647 883.572 1.042.708 1.363.750 1.595.833 - -
Kuda - 327.778 400.000 450.000 741.657 - -
Babi - - 314.223 347.411 475.587 516.101 -
Kambing - - - 78.791 135.243 - -
Produsen:
Kerbau 445.042 478.889 557.505 622.167 1.099.231 1.364.033 1.658.167
Sapi 455.250 502.917 584.474 656.451 934.991 1.294.363 1.680.358
Kuda 284.364 311.203 301.312 379.938 715.053 762.150 975.564
Kambing 46.083 50.675 56.198 64.530 97.994 141.537 170.235
Babi 174.875 190.400 210.358 232.257 373.398 491.120 649.129
Ayam kpg 7.833 8.719 10.166 12.655 17.535 23.474 27.341
Sumber: BPS (2001)
Ancaman dan peluang pengembangan agribisnis peternakan
Produktivitas ternak merupakan gabungan sifat produksi dan reproduksi, serta dapat ditingkatkan melalui perbaikan mutu genetik atau seleksi dan hasil perkawinan serta perbaikan lingkungan secara terpadu (LASLEY, 1978; WAWICK et al., 1993; HARDJOSUBROTO, 1994) dalam (SUMADI, 2002). Untuk mencapai program yang sesuai dengan tujuan perencanaan program maka paradigma baru yang dianut adalah terlebih dahulu dilakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). Apabila analisis SWOT telah dilakukan maka dibuatlah suatu perencanaan yang mantap untuk jangka panjang, menengah maupun pendek (WIRDAHAYATI et al., 2001 dan SUMADI, 2002). Dari analisis tersebut diperoleh beberapa kriteria antara lain:
1. Strength (kekuatan atau keunggulan): (1) plasma nutfah ternak potong, seperti sapi Bali, Sumba Ongole dan kerbau, (2) tersedia ternak yang cukup banyak, (3) jumlah ternak yang cukup besar yang telah terorganisir dalam kelompok-kelompok peternak pada semua wilayah, (4) masih tersedia lahan yang dapat dikembangkan
sebagai padang penggembalaan dan sumber pakan, (5) pelaksanaan IB yang makin berkembang, dan (6) semua pelaku otonomi (swasta, koperasi, BUMN/BUMD) dan pemerintah ingin mengembangkan dan melestarikan ternak di NTT, (7) sapi Bali dikenal merupakan salah satu sapi asli Indonesia yang mempunyai ciri-ciri kebaikan, terutama dalam hal produktivitas. Hasil penelitian (ROSNAH, 1998, dalam SUMADI, 2002) bahwa sapi Bali di Timor Barat mempunyai jarak beranak 15,59 bulan (setara dengan angka kelahiran sebesar 76,97% dari induk per tahun). Selanjutnya di Propinsi Bali angka kelahiran sapi Bali sebesar 60,73% dari induk atau 25% dari populasi. Kelebihan lain dari sapi Bali adalah bahwa sapi Bali secara politik, merupakan aset nasional berupa sumber genetik yang tidak ada duanya. Disamping itu dari aspek bisnis, para jagal di Jakarta sangat menyukai sapi Bali karena kualitas dagingnya sesuai selera konsumen dan kualitasnya mempunyai nilai yang tinggi. Harga sapi ini bahkan paling tinggi dibandingkan sapi impor atau sapi lokal lainnya, dan (8) sapi Sumba Ongole yang dipelihara secara penggemukan mempunyai ADG 0,85 kg, konversi pakan

Lokakarya Nasional Sapi Potong 2004
174
10,60, persentase karkas 52,69% dan daging 77,31% dari berat karkas (SUMADI, 2002).
2. Weaknes (kelemahan): (1) belum adanya program pelestarian plasma nutfah yang mantap, (2) belum adanya kelompok peternak yang berdasar hukum dan menjalankan fungsi manajemen secara agribisnis, (3) produktivitas ternak yang masih relatif rendah, (4) adanya tendensi negatif di beberapa tempat, (5) sistem peternakan yang sebagian besar masih tradisional dan sambilan, dan (6) belum adanya ranch yang memadai, (7) sapi Bali mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu dalam hal kecepatan pertumbuhan dan ukuran tubuh. Disamping itu disinyalir adanya seleksi negatif dan inbreeding (karena penggunaan pejantan yang lama) baik pada sapi Bali atau Sumba Ongole, dan (8) sapi Sumba Ongole mempunyai jarak beranak yang relatif panjang (dapat mencapai 24 bulan) dan beranak pertama pada umur 3-4 tahun. Sapi Bali peka terhadap penyakit Jembrana dan penyakit virus lainnya. Sapi Bali disilangkan dengan sapi bangsa lain, maka keturunan yang jantan akan majir.
3. Oportunity (peluang): (1) permintaan pasar akan daging dan produk ternak lainnya yang terus meningkat, (2) adanya keinginan peternak untuk mendapatkan sapi yang cepat besar dan cepat jual, yang berakibat meningkatnya permintaan akan bibit ternak dan sapi bakalan untuk digemukkan.
Jumlah pemotongan sapi di Indonesia ± 1,5 juta ekor dan produksi dalam negeri sebesar ± 1,2 juta ekor per tahun. Jadi kekurangan sebesar 0,3 juta per tahun dan dicukupi dari impor. Disamping itu semakin meningkatnya permintaan akan ternak dan produk ternak yang berkualitas.
4. Threat (tantangan): (1) era globalisasi, akan ada persaingan bebas dengan negara penghasil sapi potong dan daging, (2) otonomi daerah yang diartikan adanya desentralisasi secara mutlak.
Hasil analisis SWOT tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif agribisnis diperlukan peningkatan produktivitas ternak untuk
memenuhi permintaan pasar. Peningkatan produktivitas ternak baik dari segi kuantitas dan kualitas, sekaligus diikuti peningkatan efisiensi usaha sehingga produk yang dijual sangat kompetitif.
ARAH DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN
Arah dan kebijakan pengembangan peternakan NTT
Pengembangan teknologi
Meskipun sektor peternakan di NTT memberikan sumbangan sebesar 10,26% pada tahun 2001 terhadap PDRB, tetapi sampai sekarang pelaksanaannya masih bersifat ekstensif tardisional. Sebagian besar ternak di NTT masih dipelihara dengan cara dilepas di padang pengembalaan tanpa pemeliharaan kesehatan. Kualitas produk peternakan pada umunya masih rendah. Penggunaan obat-obatan dan vaksinasi masih terbatas di daerah yang relatif maju. Sapi Bali dikenal mempunyai fertilitas yang relatif tinggi dengan persentase kelahiran anak setiap tahunnya 70-80% (PHILPS, 1986; WIRDAHAYATI, 1994, WIRDAHAYATI et al., 2000). Tetapi angka kelahiran yang tinggi ini diikuti juga oleh tingginya angka angka kematian anak sapi (20-50%) tergantung dari lamanya musim kemarau (WIRDAHAYATI et al., 2000). Kematian anak sapi Bali tertinggi ditemukan pada umur < 1 bulan (36%), diikuti pada umur < 6 bulan (29%) dan pada umur enam (6) bulan sampai satu (1) tahun (27%), sedangkan kematian anak sapi berumur > 1 tahun hanya sebesar 9%. Demikian pula dengan tambahan berat badan ternak yang dilepas di padang penggembalaan hanya 0,1−0,2kg/hari, sehingga untuk mencapai berat ideal untuk diperdagangkan antar pulau dengan standar lebih dari 250 kg, memerlukan waktu lama. Apabila sistem pemeliharaan dengan intensif berupa pemberian pakan ternak yang baik dan pemberian probiotik, penggemukan dapat mencapai 0,4-0,6 kg/hari, sehingga berat optimal lebih cepat tercapai (MARAWALI et al., 2002).
Pengembangan teknologi kandang kelompok dinilai sangat baik terutama karena

Lokakarya Nasional Sapi Potong 2004
175
kebersihan dari kotoran ternak dapat dijaga, kehilangan ternak di tekan sekecil mungkin, dan pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk kandang lebih mudah karena kandang biasanya disekitar perkampungan. Penggunaan padang penggembalaan yang lebih baik lebih bersifat kelembagaan sosial dari dari pada teknologi. Cara pengembalaan yang sekarang dilakukan selain telah merusak padang pengembalaan, juga tidak menunjang perkembangan usahatani tanaman, karena tanaman banyak dirusak oleh ternak yang dilepas di padang pengembalaan (GUNAWAN dan YUSDJA, 1991).
Peningkatan pengetahuan petani dalam hal teknis harus disertai dengan pengingkatan pengetahuan dalam pengembangan usaha, memanfaatkan kesempatan ekonomi dan pasar, melihat prospek dan perubahan pada masa yang akan datang. Selain itu perlu meningkatkan pengertian akan pentingnya pola produksi yang menerapkan pola pertanian terpadu agar terjadi optimalisasi pemanfatan sumberdaya.
Untuk meningkatkan produktivitas ternak di NTT faktor makanan perlu diperhatikan. Teknologi di bidang peternakan sudah banyak yang tersedia seperti jenis-jenis tanaman makanan ternak unggul untuk lahan kering iklim kering, teknologi pengawetan pakan, teknologi pakan tambahan sumber protein dan mineral, namun untuk mempercepat adopsi teknologi tersebut dibutuhkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak terkait dalam usaha peternakan guna memberikan prioritas yang tinggi terhadap apklikasi teknologi di tingkat petani peternak.
Pengembangan kelembagaan
Kelembagaan pendukung pengembangan peternakan di NTT seperti Penyuluh, relatif tertinggal dibandingkan di Pulau Jawa. Kelembagaan penyuluh di NTT misalnya, dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, penyelenggaraan penyuluhan yang tadinya merupakan wewenang pusat dan sekarang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemda. Persoalannya adalah sistem penyuluhan pertanian yang berlangsung di setiap kabupaten bervariasi, dimana ada yang berpayung pada Dinas lingkup pertanian, ada yang di bawah Badan Bimas Ketahanan Pangan (B2KP)
kabupaten, dan ada sebagian yang di Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian (KIPP). Hasil survai (BUDIANTO et al., 2003) menunjukkan bahwa Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang merupakan basis penyuluhan di pedesaan, ternyata saat ini banyak yang tidak berfungsi lagi, bangunannya banyak yang rusak dan sarana yang dimiliki sudah tidak berfungsi bahkan tidak ada lagi. Keberadaan kelembagaan penyuluhan dan penyuluh pertanian di NTT dapat disajikan pada (Tabel 7).
Kelembagaan kelompok tani yang mempunyai hubungan fungsional dengan penyuluh pertanian lapangan relatif tertinggal bila dibandingkan dengan di daerah Barat. Salah satu penyebab kurang intensifnya aktivitas kelompok tani terutama di lahan kering seperti NTT adalah belum ditemukannya perekat dalam kelompok tani (PASANDARAN et al., 1993 dalam DIWYANTO et al., 1995). Selanjutnya dikatakan bahwa di lahan sawah yang menjadi perekatnya adalah air. Mungkin di NTT yang dapat dijadikan perekatnya adalah cathment area dan bangunan konservasi. Untuk kelompok ternak pengembangan diarahkan melalui lomba produksi ternak dan tanaman pakan pakan ternak di tingkat kelompok tani/desa setiap tahun guna merangsang petani untuk meningkatkan populasi dan produktivitas ternak.
Tabel 7. Kelembagaan penyuluh di Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Timur Lembaga penyuluhan dan penyuluh
Jumlah kabupaten
Jumlah BIPP aktif
BIPP 14 9 yaitu: Kupang, TTU, Alor, Lembata, Ende, Ngada, Manggarai, Sumba Timur dan Sumba Barat
BPP - 46 Kelompok tani : 4.919
Dewasa 4.592 Wanita 149 Taruna 178
Penyuluh 857
Sumber: BALUKH (2001)

Lokakarya Nasional Sapi Potong 2004
176
Kelembagaan infrastruktur seperti transportasi, pasar, tempat pemotongan ternak dan penyimpanan masih sangat sederhana dan dapat dikatakan belum menunjang perkembangan peternakan yang mengarah pada pemeliharaan dan pemasaran yang intensif. Perlunya peningkatan kinerja aparatur pemerintah dan optimalisasi pemanfaatan sarana terutama pemeliharaannya agar dapat menunjang kegiatan rutin maupun pembangunan. Selain itu diupayakan pemberdayaan UPTD dalam rangka meningkatkan PAD. Aparatur teknis di lapangan agar terus dilatih Pembantu Petugas Peternakan Mandiri (P3M) bagi petani terpilih di desa untuk membantu melakukan pelayanan di desanya dengan insentif dari masyarakat sendiri.
Kebijakan yang diperlukan
Berdasarkan Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Daerah dan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) serta Rencana Strategis Pembangunan Daerah NTT 2000-2004 maka arah kebijakan umum pembangunan sub sektor peternakan NTT adalah peningkatan produksi dan produktivitas peternakan.
Memperhatikan arah kebijakan umum tersebut maka strategi yang akan dilakukan untuk mencapainya adalah sebagai berikut : (i) pengembangan wilayah berdasarkan komoditas ternak unggulan, (ii) pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan, (iii) optimalisasi peranan berbagai kelembagaan dan (iv) pengembangan kemitraan yang luas dan saling menguntungkan.
Mengacu pada kebijakan nasional pembangunan pertanian melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Agribisnis, maka dijabarkan dalam beberapa program di tingkat propinsi NTT sebagai berikut:
1. Program pembibitan ternak, dengan tujuan meningkatkan produksi dan produktivitas ternak. Kegiatan prioritas yaitu: (1) pengembangan kawasan pembibitan ternak di pedesaan, (2) pembuatan pagar hidup dan perbaikan padang penggembalaan, (3) Pengolahan dan pengawetan pakan ternak,
dan (4) meningkatkan manajemen usaha ternak kecil dan unggas
2. Program pengamanan ternak, dengan tujuan meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular. Kegiatan prioritas: (1) pengamatan penyakit hewan menuluar, (2) pencegahan penyakit hewan melalui vaksinasi, (3) pemberantasan penyakit melalui pengobatan dan upaya lainnya seperti pemusnahan reaktor dan eliminasi, dan (4) pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dan sosialisasi konsumsi produk ternak.
3. Program pengembangan SDM dan kelembagaan peternakan, dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan kemampuan sumberdaya manusia peternakan. Kegiatan prioritas: (1) pembinaan personalia dan ketatausahaan, (2) pendidikan dan latihan aparatur, (3) optimalisasi peranan unit pelaksana teknis, (4) optimalisasi peranan kelompok tani ternak, dan (5) pemberdayaan masyarakat melalui penguatan modal usaha kelompok.
4. Program pembinaan petani, pembinaan petani dimaksudkan untuk mengubah cara pandang terhadap ternak. Diharapkan perubahan ini berpengaruh positif terhadap upaya peningkatan produksi dan adopsi teknologi peternakan dapat dipercepat. Sebagai dasar pembinaan dilakukan: (1) inventarisasi ternak dan pengumpulan data dasar peternakan, meliputiproduktivitas dan reproduktivitas tiap jenis ternak, (2) motivasi pemeliharaan ternak, hasil studi digunakan untuk mengarahkan usaha ternak yang lebih berorientasi pada pendapatan serta mengidentifikasi pra kondisi yang dibutuhkan untuk merangsang pengembang-an peternakan, (3) daya tampung wilayah, bertujuan untuk menentukan populasi optimal setiap wilayah/penggunaan tanah yang berbeda dan menentukan struktur ternak yang ideal. Selain itu dapat pula digunakan untuk dasar pertimbangan kegiatan penyebaran ternak, dan (4) pewilayahan ternak dan identifikasi model farming system, daya dukung wilayah dan jenis ternak yang paling menguntungkan untuk dikembangkan di wilayah tertentu

Lokakarya Nasional Sapi Potong 2004
177
diidentifikasi. Hal ini digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam merancang model farming system.
5. Program pengembangan sarana dan prasaran peternakan, dengan tujuan meningkatkan pembinaan organisasi pemasaran dan industri pengolahan produk ternak. Kegiatan prioritas: (1) pembinaan organisasi profesi, (2) pengembangan sistem informasi peternakan, (3) pengadaan sarana dan prasarana peternakan, (4) melengkapi sarana dan prasarana kelembagaan, dan (5) meningkatkan pemanfaatan teknologi pengolahan produk peternakan.
PENUTUP
Manajemen pemeliharaan ternak sapi petani di NTT masih bersifat ektensif tradisional dengan memanfaatkan rumput alam dan padang pengembalaan yang ada. Walaupun demikian ternak memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan akan daging sapi regional maupun kebutuhan daging Nasional. Rendahnya produktivitas ternak sapi serta kompleksnya masalah yang ditemui di dalam sistem usaha ternak merupakan potensi dan peluang untuk pengembangan usaha ternak sapi. Oleh karena itu dibutuhkan pemikiran dan usaha yang serius dalam meningkatkan produktivitas ternak sapi. Mudah-mudah makalah ini dapat bermanfaat bagi kita, pembaca dan pengguna lainnya. Saran dan kritikan yang konstruktif kami ucapkan terima kasih.
DAFTAR PUSTAKA
ANONYM. 1998. Program Pengembangan Sub-Sektor Peternakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Timur.
ANONYM. 1993. Statistik Pertanian Nusa Tenggara Timur, BPS.
AL ATAS, F. 1983. Komposisi Kimia Beberapa Daun-daun Makanan Ternak Pada Musim Kemarau di Bali. Thesis Fakultas Peternakan Universitas Udaya Denpasar.
ASNATH, M.F., YUSUF dan U. BAMUALIM. 1993. Survai Produksi Ternak Kecil di Desa Naibonat, Camplong I dan Camplong II
Kabupaten Kupang. Publikasi Wilayah Kering 1 (1). 1993. Badan Litbang Pertanian Deptan. Proyek P3NT/NTASP.
BAMUALIM, A. dan E.O. MOMUAT, 1991. Pemanfaatan Batang Pohon Gewang Sebagai Pakan Ternak Sapi dan Kambing. Seri Pembangunan No. 13, Badan Litbang Pertanian.
BALUKH, J.M. 2001. Peran Kelembagaan Penyuluhan Dalam Proses Percepatan Adopsi Teknologi Pertanian di Nusa Tenggara. Makalah Disampaikan Dalam Seminar Regional Peningkatan Kinerja BPTP dan Komunikasi Hasil-hasil Penelitian Mendukung Pembangunan Pertanian di Nusa Tenggara, Kupang, 2-3 November 2001.
BAMUALIM, A. dan A. SALEH. 1992. Produksi dan Kualitas Hijauan Makanan Ternak di Nusa Tenggara. Anuan Assessment Meeting, EIVS Project, 15–18 September 1992. Mataram–Lombok.
BAMUALIM, A. dan UMBU P. SARAMONY, 2001. Produksi Peternakan di Wilayah Semiarid Nusa Tenggara Timur. Pembangunan Pertanian di Wilayah Kering Indonesia. Prosiding Konferensi Internasional Pembangunan Pertanian Semi Arid Nusa Tenggara Timur, Timor Timur dan Maluku Tenggara, 10–16 Desember 1995 di Kupang.
BPS. 2001. Indikator Ekonomi Nusa Tenggara Timur. BPS Propinsi NTT.
------, 2001. Statistik Harga Produsen Nusa Tenggara Timur 2001. BPS Propinsi NTT.
BUDIANTO A.B., A. ILLA, M. RATNADA, W.Y. COSTA dan I.K. GEDE SUBAGIA. 2003. Kajian Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Era Otonomi Daerah di NTT. Balai Agribisnis Ternak Potong dan Teknologi Lahan Kering Noelkabi bekerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTT.
DINAS PETERNAKAN SUMBA TIMUR. 1989. Program Pengembangan Subsektor Peternakan. Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Timur.
DINAS PETERNAKAN PROPINSI NTT. 2001. Statistik Pertanian Nusa Tenggara Timur 2001. BPS Propinsi NTT.
DIWYANTO, K. dan B. R. PRAWIRADIPUTRA, 1995. Keunggulan Komparatif Lahan Kering Sebagai Wilayah Pengembangan Peternakan. Prosiding Seminar Komunikasi dan Aplikasi Hasil Penelitian Peternakan Lahan Kering. Sub Balai Penelitian Ternak Lili–Kupang, Badan Litbang Pertanian. 17–18 Nopember 1995.

Lokakarya Nasional Sapi Potong 2004
178
GUNAWAN, M. dan YUSMICHAD YUSDJA. 1991. Sumberdaya Manusia Dalam Penggunaan Peternakan di Indonesia Bagian Timur. Simposium Perencanaan Pembangunan Peternakan di NTB, NTT dan Timor Timur Kerjasama dengan Biro Perencanaan Deptan dengan Australia International Development Assistance Bureau, Mataram 20−23 Januari 1991.
KASRYNO, F. 1997. Strategi dan Kebijaksanaan Penelitian dalam Menunjang Pembangunan Peternakan. Prosiding Seminar Nasioanal Peternakan dan Veteriner. Jilid I. Puslitbang Peternakan, Badan Litbang Pertanian, Deptan. Bogor, 18–19 Nopember 1997.
MARAWALI, H.H. 2002. Analisis Penggemukan Sapi Potong Dalam Program Sistem Usaha Pertanian di Kabupaten Kupang. Thesis Program Pascasarjana UGM Yogyakarta, 2002.
NULIK, J. dan A. BAMUALIM. 1998. Pakan Ruminansia Besar di Nusa Tenggara. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Naibonat Bekerjasama Eastern IslandsVeterinary Services Project.
PELLOKILA, S.CH., U. GINTING dan F.J.J. NISNONI. 1991. Potensi Sumberdaya Alam Dan ternak Serta Permasalahannya Dalam Pembangunan Peternakan di NTT. Simposium Perencanaan Pembangunan Peternakan di NTB, NTT dan Timor Timur Kerjasama dengan Biro Perencanaan Deptan dengan Australia International Development Assistance Bureau, Mataram 20-23 Januari 1991.
RANTETANA, M.H. dan T.A. NAPITUPULU, 1991. Perdagangan Ternak Regional, Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Datang. Simposium Perencanaan Pembangunan Peternakan di NTB, NTT dan Timor Timur Kerjasama dengan Biro Perencanaan Deptan dengan Australia International Development Assistance Bureau, Mataram 20-23 Januari 1991.
SUMADI. 2002. Aspek Peningkatan Mutu Genetik dan Reproduksi Ternak Dalam Perspektif Agribisnis. Seminar Nasional Pengembangan Peternakan Rakyat Dalam Perspektif Agribisnis, Fakultas Peternakan Undan, Kupang, 29 Oktober 2002.
STATISTIK PETERNAKAN. 2002. Statistik Peternakan Propinsi Tahun 2002. Dinas Peternakan Propinsi NTT.
STATISTIK PETERNAKAN. 2003. Statistik Peternakan Propinsi Tahun 2003. Dinas Peternakan Propinsi NTT.
WIRDAHAYATI, R.B., FERNANDEZ, P.TH., LIEM C. and A. BAMUALIM. 2000. Termination Report on ACIAR Project No. 9312.
WIRDAHAYATI, R.B., YUSUF, B. DE ROSARI. P.TH. FERNANDEZ, P. TANYA dan MELATI. 2001. Evaluasi dan Prospek Pengembangan Sapi Brahman di Kabupaten Sumba Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur.
YUSUF, B. DE ROSARI dan C. LIE, 2000. Pemasaran Ternak Sapi Bali di Nusa Tenggara. Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. 5(1), Januari 2002. Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang, Deptan.