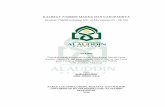LI 2
-
Upload
tarsiah-ningsih-ii -
Category
Documents
-
view
215 -
download
2
description
Transcript of LI 2

Nama : Tarsiah Ningsih NIM : 030 13 186
Kasus : 2 Modul : GHPO
1. Anatomi dan histologi
Hepar terdiri atas :
lobus dexter
lobus sinister
lobus caudatus
lobus quadratus
Pada sisi anterosuperior oleh lig. Falsiformis dibagi menjadi lobus dekstra dan sinistra. Pada sisi
posterior, lobus kaudatus terletak diantara v . cava inferior dan fissura lig. Venosum . Lobus kuadratus
terletak antara fossa vesika fellea dan fissura lig. Teres.
Batas hepar
Batas atas sejajar dengan ruangan interkostal V kanan
Batas bawah menyerong ke atas dari iga IX kanan ke iga VIII kiri
Perdarahan
Vena hepatica
Vena cava inferior
Arteri hepatica
Vena porta hepatis
Persarafan
N. simpatikus : dari ganglion seliakus, berjalan bersama pembuluh darah pada lig.
hepatogastrika dan masuk porta hepatis
N. Vagus : dari trunkus sinistra yang mencapai porta hepatis mneyusuri kurvatura minor
gaster dalam omentum.

Histologi Hati
Sel–sel yang terdapat di hati antara lain: hepatosit, sel endotel, dan sel makrofag yang disebut
sebagai sel kuppfer, dan sel ito (sel penimbun lemak). Sel hepatosit berderet secara radier dalam lobulus
hati. Celah diantara lempeng-lempeng ini mengandung kapiler yang disebut sinusoid hati.
Sinusoid hati adalah saluran yang berliku–liku dan melebar, dibatasi oleh 3 macam sel, yaitu sel
endotel (mayoritas) dengan inti pipih gelap, sel kupffer yang fagositik dengan inti ovoid, dan sel stelat
atau sel Ito atau liposit hepatik yang berfungsi untuk menyimpan vitamin A dan memproduksi matriks
ekstraseluler serta kolagen. Aliran darah di sinusoid berasal dari cabang terminal vena portal dan arteri
hepatik, membawa darah kaya nutrisi dari saluran pencernaan dan juga kaya oksigen dari jantung
Traktus portal terletak di sudut-sudut heksagonal. Pada traktus portal, darah yang berasal dari vena
portal dan arteri hepatik dialirkan ke vena sentralis. Traktus portal terdiri dari 3 struktur utama yang
disebut trias portal. Struktur yang paling besar adalah venula portal terminal yang dibatasi oleh sel
endotel pipih. Kemudian terdapat arteriola dengan dinding yang tebal yang merupakan cabang terminal
dari arteri hepatik. Dan yang ketiga adalah duktus biliaris yang mengalirkan empedu. Selain ketiga
struktur itu, ditemukan juga limfatik. Cairan empedu yang dihasilkan oleh hepar berasal dari ducti biliferi
akan berkumpul dalam ductus hepaticus communis yang melanjutkan menjadi ductus cysticus yang
bermuara dalam vesica fellea. Cairan empedu yang dibutuhkan untnuk pencernaan akan disalurkan
melalui ductus choledochus dan bermuara dalam duodenum.
2. Kondisi penyebab hipoksia dan asidosis metabolic pada neonatesBeberapa faktor tertentu diketahui dapat menjadi penyebab terjadinya asfiksia pada bayi baru lahir, diantaranya : 1. Faktor Ibu
Wanita yang berumur 15 tahun atau lebih muda meningkatkan risiko preeklamsi (sebuah tipe tekanan darah tinggi yang berkembang selama kehamilan).Wanita yang berumur 35 tahun atau lebih meningkat risikonya dalam masalah-masalah seperti tekanan darah tinggi, gestasional diabetes (diabetes yang berkembang pada saat kehamilan) dan komplikasi selama kehamilan.
Perdarahan antepartum merupakan perdarahan pada kehamilan diatas 22 minggu hingga menjelang persalinan yaitu sebelum bayi dilahirkan.Komplikasi utama dari perdarahan antepartum adalah perdarahan yang menyebabkan anemia dan syok yang menyebabkan keadaan ibu semakin jelek. Keadaan ini yang menyebabkan gangguan ke plasenta yang mengakibatkan anemia pada janin bahkan terjadi syok intrauterin yang mengakibatkan kematian janin intrauterine.
Demam selama persalinan infeksi berat (malaria, sifilis, TBC, HIV) Kehamilan postdate (sesudah 42 minggu kehamilan), anemia, paritas, dsb.

2. Faktor Plasenta Pertukaran gas antara ibu dan janin dipengaruhi oleh luas kondisi plasenta. Gangguan pertukaran gas di plasenta yang akan menyebabkan asfiksia janin. Fungsi plasenta akan berkurang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan O2 dan menutrisi metabolisme janin. Asfiksia janin terjadi bila terdapat gangguan mendadak pada plasenta.Kemampuan untuk transportasi O2 dan membuang CO2 tidak cukup sehingga metabolisme janin berubah menjadi anaerob dan akhirnya asidosis dan PH darah turun.a. Lilitan tali pusat. b. Tali pusat pendek. c. Simpul tali pusat. d. Prolapsus tali pusat.
3. Faktor Bayi Bayi prematur (sebelum 37 minggu kehamilan). Berat Bayi Lahir (BBL) Kelainan bawaan Meconium
4.Faktor Persalinan1. Pemakaian obat analgesi/ anastesi yang berlebihan2. Trauma persalinan, misalnya perdarahan intrakranial.3. letak sungsang
3. Pemeriksaan penunjang Bilirubin serum total. Bilirubin serum direk dianjurkan untuk diperiksa bila ikterus
menetap sampai usia >2 minggu atau dicurigai adanya kolestasis. Darah perifer lengkap dan gambaran apusan darah tepi untuk melihat morfologi
eritrosit dan ada tidaknya hemolisis. Bila fasilitas tersedia, lengkapi dengan hitung retikulosit.
Golongan darah, Rhesus, dan direct Coombs’ test dari ibu dan bayi untuk mencari penyakit hemolitik. Bayi dari ibu dengan Rhesus negatif harus menjalani pemeriksaan golongan darah, Rhesus, dan direct Coombs’ test segera setelah lahir.
Kadar enzim G6PD pada eritrosit. Pada ikterus yang berkepanjangan, lakukan uji fungsi hati, pemeriksaan urin untuk
mencari infeksi saluran kemih, serta pemeriksaan untuk mencari infeksi kongenital, defek metabolik, atau lainnya.
4. Faktor resikoFaktor risiko untuk timbulnya ikterus neonatorum:
Faktor Maternal a. Ras atau kelompok etnik tertentu (Asia, Native American,Yunani) b. Komplikasi kehamilan (DM, inkompatibilitas ABO dan Rh) c. Penggunaan infus oksitosin dalam larutan hipotonik. d. ASI

Faktor Perinatal a. Trauma lahir (sefalhematom, ekimosis) b. Infeksi (bakteri, virus, protozoa)
Faktor Neonatus a. Prematuritas b. Faktor genetik c. Polisitemia d. Obat (streptomisin, kloramfenikol, benzyl-alkohol, sulfisoxazol) e. Rendahnya asupan ASI f. Hipoglikemia g. Hipoalbuminemia
5. Tatalaksana Ikterus Fisiologis
Untuk mengatasi ikterus pada bayi yang sehat, dapat dilakukan beberapa cara berikut: Minum ASI dini dan sering Terapi sinar, sesuai dengan panduan WHO Pada bayi yang pulang sebelum 48 jam, diperlukan pemeriksaan ulang dan kontrol lebih
cepat (terutama bila tampak kuning).
Tata laksana Awal Ikterus Neonatorum (WHO) Mulai terapi sinar bila ikterus diklasifikasikan sebagai ikterus berat. Tentukan apakah bayi memiliki faktor risiko berikut: berat lahir < 2,5 kg, lahir
sebelum usia kehamilan 37 minggu, hemolisis atau sepsis. Ambil contoh darah dan periksa kadar bilirubin serum dan hemoglobin, tentukan
golongan darah bayi dan lakukan tes Coombs: Bila kadar bilirubin serum di bawah nilai dibutuhkannya terapi sinar, hentikan terapi sinar. Bila kadar bilirubin serum berada pada atau di atas nilai dibutuhkannya terapi sinar, lakukan terapi sinar. Bila faktor Rhesus dan golongan darah ABO bukan merupakan penyebab hemolisis atau bila ada riwayat defisiensi G6PD di keluarga, lakukan uji saring G6PD bila memungkinkan.
Tentukan diagnosis banding
Tata laksana Hiperbilirubinemia Hemolitik. Paling sering disebabkan oleh inkompatibilitas faktor Rhesus atau golongan
darah ABO antara bayi dan ibu atau adanya defisiensi G6PD pada bayi. Bila nilai bilirubin serum memenuhi kriteria untuk dilakukannya terapi sinar, lakukan terapi sinar . Bila rujukan untuk dilakukan transfusi tukar memungkinkan
Ikterus Berkepanjangan (Prolonged Jaundice). Diagnosis ditegakkan apabila ikterus menetap hingga 2 minggu pada neonatus cukup bulan, dan 3 minggu pada neonatus kurang bulan. Terapi sinar dihentikan, dan lakukan pemeriksaan penunjang untuk mencari penyebab.

6. KomplikasiKelainan yang mungkin timbul karena terapi sinar antara lain:
a. Peningkatan kehilangan cairan tubuh bayi. Karena itu pemberian cairan harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Bila bayi bisa minum ASI, sesering mungkin berikan ASI. b. Frekwensi buang air besar meningkat karena hiperperistaltik (gerakan usus yang meningkat). c. Timbul kelainan kulit yang bersifat sementara pada muka, badan, dan alat gerak. d. Kenaikan suhu tubuh. e. Kadang pada beberapa bayi ditemukan gangguan minum, rewel, yang hanya bersifat sementara.
Komplikasi biasanya bersifat ringan dan tidak sebanding dengan manfaat penggunaannya. Karena itu terapi sinar masih merupaka pilihan dalam mengatasi hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir.
7. PrognosisHiperbilirubemia baru akan berpengaruh buruk apabila bilirubin indirek telah melalui sawar otak.
Referensi :
1. Hull D., Johnston D.I. Dasar-dasar pediatri. EGC. 2008; Jakarta: Edisi ke-3: hal 61-4;168-70
2. Ambarwati, E dan Rismintari, Y. Asuhan Kebidanan Komunitas. Yogyakarta: Nuha Medika. 2009
3. Surjono A. Hiperbilirubinemia pada neonatus:pendekatan kadar bilirubin bebas. Berkala Ilmu Kedokteran 1995;27:43-6
4. American Academy of Pediatrics. Clinical Practice Guideline. Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation. Pediatrics 2004;114:297-316.