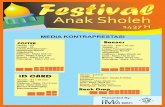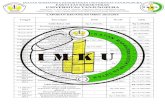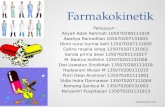Laporan Kasus FIXX
-
Upload
dhinie-noviani -
Category
Documents
-
view
10 -
download
1
description
Transcript of Laporan Kasus FIXX
Laporan Kasus
SIROSIS HEPATIS DEKOMPENSATA STADIUM 3
ET CAUSA HEPATITIS B KRONIS
Disusun Oleh:
Reynatta Audralia Namara
NIM: 030.10.234
Pembimbing:
dr. Irwin, Sp.PD
KEPANITERAAN KLINIK SMF PENYAKIT DALAM
RSUD KARAWANG
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI
JAKARTA
PENDAHULUAN
Istilah sirosis hepatis diberikan oleh Laence tahun 1819, yang berasal dari kata
Khirros yang berarti kuning orange (orange yellow), karena perubahan warna pada
nodul-nodul yang terbentuk. Sirosis hepatis adalah penyakit hepar menahun difus
ditandai dengan adanya pembentukan jaringan ikat disertai nodul yang mengelilingi
parenkim hepar.
Gejala klinis dari sirosis hepatis sangat bervariasi, mulai dari tanpa gejala sampai
dengan gejala yang sangat jelas. Gejala patologik dari sirosis hepatis mencerminkan
proses yang telah berlangsung lama dalam parenkim hepar dan mencakup proses fibrosis
yang berkaitan dengan pembentukan nodul-nodul regeneratif. Kerusakan dari sel-sel
hepar dapat menyebabkan ikterus, edema, koagulopati, dan kelainan metabolik lainnya.
Secara lengkap, sirosis hepatis adalah suatu penyakit dimana sirkulasi mikro,
anatomi pembuluh darah besar dan seluruh sistem arsitektur hepar mengalami perubahan
menjadi tidak teratur dan terjadi penambahan jaringan ikat (fibrosis) di sekitar parenkim
hepar yang mengalami regenerasi.
Menurut Ali, angka kasus penyakit hati menahun di Indonesia sangat tinggi. Jika
tidak segera diobati, penyakit itu dapat berkembang menjadi sirosis atau kanker hati,
sekitar 20 juta penduduk Indonesia terserang penyakit hati menahun. Angka ini
merupakan perhitungan dari prevalensi penderita dengan infeksi hepatitis B di Indonesia
yang berkisar 5-10 persen dan hepatitis C sekitar 2-3 persen. Dalam perjalanan
penyakitnya, 20-40 persen dari jumlah penderita penyakit hati menahun itu akan menjadi
sirosis hati dalam waktu sekitar 15 tahun, tergantung sudah berapa lama seseorang
menderita hepatitis menahun itu.
Sirosis hepatis merupakan penyakit yang sering dijumpai di seluruh dunia
termasuk di Indonesia, kasus ini lebih banyak ditemukan pada kaum laki-laki
dibandingkan kaum wanita dengan perbandingan 2-4 : 1 dengan umur rata-rata terbanyak
antara golongan umur 30-59 tahun dengan puncaknya sekitar 40-49 tahun.
BAB I
STATUS PASIEN
1.1 IDENTITAS PASIEN
Nama : Tn. Kusnadi
Jenis Kelamin : Laki- laki
TTL : 04/09/1961
Umur : 53 tahun 3 bulan 15 hari
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : -
Agama : Islam
Status Pernikahan : Kawin
Alamat : Dusun Gardu Jaya, Desa Gompangsari
No.RM : 00.56.92.45
Tanggal masuk : 19 Desember 2014
DPJP : dr. Budowin, Sp.PD
1.2 ANAMNESIS
Dilakukan autoanamnesis pada tanggal 22 Desember 2014 pukul 16.30 WIB di Ruang Rengasdengklok, Rumah Sakit Umum Daerah Karawang.
Keluhan Utama
Bengkak di perut 3 hari SMRS.
Keluhan Tambahan
BAB mencret, >4x, warna merah kehitaman seperti aspal, BAK warna seperti teh, mual
(+)
Riwayat Penyakit Sekarang
3 hari SMRS OS baru menyadari bahwa perutnya membuncit, sesak (-). Awalnya OS
mengeluh BAB mencret >4x, warna merah kehitaman seperti aspal pada hari Sabtu
(20/12/2014), frekuensi semakin meningkat sampai hari Senin (22/12/2014), mual (+),
muntah (-), BAK seperti warna teh, demam (+) sampai 40° hari Minggu (21/12/2014),
dan sudah turun pada hari Senin (22/12/2014). OS juga mengeluh mata dan kulit
berwarna kuning 1 minggu SMRS.
Riwayat Penyakit Dahulu
OS belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya.OS mempunyai riwayat Diabetes
Melitus, tidak ada riwayat Hipertensi.
Riwayat Sosial dan Kebiasaan
Riwayat konsumsi alcohol (-), jamu-jamuan (-), juga tidak menggunakan jarum suntik
maupun tato, riwayat seksual tidak pernah melakukan seks bebas sebelumnya.
1.3 PEMERIKSAAN FISIK
Pemeriksaan fisik di Ruang Rengasdengklok RSUD Karawang tanggal 22 Desember
2014.
Keadaan Umum : Tampak Sakit Sedang
Kesadaran : Compos Mentis, GCS 15
Tanda Vital
Tekanan darah : 110/40 mmHg2 Nadi : 96 x/menit, regular, kuat, isi cukup, ekual Pernapasan : 26 x/menit, reguler Suhu : 38,3oC
Status Generalis
Kulit : ikterik (+) efluoresensi (-)
Kepala : normosefali, rambut hitam distribusi merata tidak mudah dicabut
Mata : konjungtiva anemis +/+, sklera ikterik +/+, RCL +/+, RCTL +/+
Telinga : normotia, serumen -/-, darah -/-
Hidung : normal, deviasi septum (-) discharge (-) pernapasan cuping hidung (-)
Mulut : sianosis (-) pucat (-), lidah tidak ada kelainan, uvula tidak dapat dinilai,
arcus faring tidak dapat dinilai, mukosa faring tidak dapat dinilai, tonsil tidak
dapat dinilai
Leher : trakea lurus tidak ada deviasi, pembersaran KGB (-), pembesaran Tiroid
(-) JVP 5+2 cm
Dinding dada: simetris
Jantung:
Inspeksi : Ictus cordis tidak terlihat
Palpasi : Ictus cordus tidak teraba
Perkusi : Batas kanan ICS IV Linea Sternalis Dextra, batas kiri ICS V, 2
jari medial linea Midclavikularis Sinistra
Auskultasi : S1 – S2 reguler, murmur (-), gallop (-)
Paru:
Inspeksi : Thoraks simetris kanan dan kiri, gerak nafas simetris kanan dan
kiri
Palpasi : Tidak dapat dinilai
Perkusi : Sonor di kedua lapang paru
Auskultasi : Vesikuller +/+ rhonki -/- wheezing -/-
Abdomen
Inspeksi : Buncit, spider nervi (-), caput medusa (-)
Palpasi :
Nyeri tekan epigastrium (+)
Undulasi (+)
Hepar teraba 3 jari dibawah arcus costae, konsistensi lunak, tidak
berbenjol-benjol, permukaan rata, tepi tumpul
Lien tidak teraba
Ballotement (-)
Perkusi :
Shifting dullness (+)
Pekak pada regio epigastrium, hipokondrium kanan dan lumbar kanan.
Timpani pada regio umbilikus, hipogastrium, lumbar kiri, inguinal kanan
dan kiri
Auskultasi : BU (+) normal
Ekstremitas :Akral teraba hangat, ikterik (+), CRT < 3 detik, edema (+)/(+)
Follow Up: 23/12/14
S: BAB mencret berkurang, lendir (+), hitam, BAK seperti teh
O: CM, TSR
TD: 115/70 mmHg HR: 96x RR:20x S: 370C
Mata : KA +/+, SI +/+
Jantung : BJ 1-2 reg. Murmur (-), Gallop (-)
Paru : Vasikuler +/+ Rhonki -/- Wheezing -/-
Abdomen : Buncit, nyeri tekan epigastrium (+), hepar teraba 3 jari dibawah arcus costae, konsistensi lunak, tidak berbenjol-benjol, permukaan rata, tepi tumpul, undulasi (+), shifting dullness (+), BU (+) normal
Ekstremitas: Akral teraba hangat, pitting oedem tungkai +/+
Follow Up: 24/12/14
S: Perut sakit dan perih
O: CM, KU TSS
TD: 100/50 mmHg HR: 84x RR: 20x S: 38,40C
Mata : KA +/+, SI +/+
Jantung : BJ 1-2 reg. Murmur (-), Gallop (-)
Paru : Vasikuler +/+ Rhonki -/- Wheezing -/-
Abdomen: Buncit, Keras, Ikterik (+), nyeri tekan epigastrium (+), hepar teraba 3 jari dibawah arcus costae, konsistensi lunak, tidak berbenjol-benjol, permukaan rata, tepi tumpul, undulasi (+), shifting dullness (+), BU (+) normal
Ekstremitas: Akral teraba hangat, pitting oedem tungkai +/+
Follow Up: 25/12/14
S: Bengkak berkurang, perut masih sakit
O: CM, KU TSS
TD: 100/70 mmHg HR: 94x RR: 20x S: 37,50C
Mata : KA +/+, SI +/+
Jantung : BJ 1-2 reg. Murmur (-), Gallop (-)
Paru : Vasikuler +/+ Rhonki -/- Wheezing -/-
Abdomen: Buncit, Keras, Ikterik (+), nyeri tekan epigastrium (+), hepar teraba 3 jari dibawah arcus costae, konsistensi lunak, tidak berbenjol-benjol, permukaan rata, tepi tumpul, undulasi (+), shifting dullness (+), BU (+) normal
Ekstremitas: Akral teraba hangat, pitting oedem tungkai +/+
Follow Up: 26/12/14
S: -
O: CM, KU TSS
TD: 110/70 mmHg HR: 86x RR: 20x S: 370C
Mata : KA +/+, SI +/+
Jantung : BJ 1-2 reg. Murmur (-), Gallop (-)
Paru : Vasikuler +/+ Rhonki -/- Wheezing -/-
Abdomen: Buncit, Keras, Ikterik (+), nyeri tekan epigastrium (+), hepar teraba 3 jari dibawah arcus costae, konsistensi lunak, tidak berbenjol-benjol, permukaan rata, tepi tumpul, undulasi (+), shifting dullness (+), BU (+) normal
Ekstremitas: Akral teraba hangat, pitting oedem tungkai +/+
Follow Up: 27/12/14
Pasien diperbolehkan pulang
1.4 PEMERIKSAAN PENUNJANG
Laboratorium
19/12/14, 23:29
Pemeriksaan Hasil Satuan Nilai normal
HEMATOLOGI
Hemoglobin
Hematokrit
Leukosit
Trombosit
9,9
27,5
19,3
27,5
g/dL
%
ribu/ul
ribu/ul
13,2-17,3
33-45
5.0-10,0
150-440
FUNGSI GINJAL
Ureum
Kreatinin
34,7
0,69
mg/dL
mg/dL
15,0 – 50,0
0,60 – 1,10
FUNGSI HATI
SGOT
SGPT
Bilirubin Direk
Bilirubin indirek
Protein Total
104,8
141,8
5,69
0,95
5,03
U/l
U/l
mg/dL
mg/dl
g/dl
s/d 37
s/d 40
s/d 0,25
s/d 0,75
6,60 – 8,70
Albumin
Globulin
2,29
2,74
mg/dl
mg/dl
3,50 – 5,00
3,10 – 3,70
DIABETES
Glukosa Darah Sewaktu 124 mg/dl < 140
23/12/14 (11:53)
Hasil USG
Hepar : Membesar, echoparenkim meningkat, tak tampak nodul
Lien, pancreas, gall blader : Tidak membesar, tak tampak nodul/batu
Ginjal kanan, kiri : Tidak membesar, batas sinus cortex kabur, tak tampak
batu
Buli-buli : Kesan normal
Tampak gambaran cairan dalam kavum abdomen
Kesan : Suspek sirosis hepatis, ascites, nephritis bilateral
1.5 DIAGNOSIS
Diagnosis kerja
Sirosis Hepatis Dekompensata Stadium 3 et causa Hepatitis B Kronik
Diagnosis banding Non-Alcoholic steatohepatitis Hepatitis C Fatty liver
1.6 TATALAKSANA
IMUNOLOGI
HBsAg Rapid Reaktif Non-reaktif
19/12/14
IUVD Dextrose 5% 500cc / 24 jam
Cefotaxim 2x1 sr PO
Furosemid 3x1 IV
Spironolacton 3x100 mg PO
Curcuma 3x1 PO
Ranitidin 2x50 mg IV
Ekstrak putih telur
20/12/14
IUVD Dextrose 5% 500cc / 24 jam
Lactulac 1x10 cc
Furosemid 3x1 IV
Spironolacton 3x100 PO
Curcuma 3x1 PO
Ranitidin 2x50 IV
Ceftriaxone 2x1 gram IV
PCT 5x1 PO
Ekstrak putih telur
21/12/14
IUVD Dextrose 5% 500cc / 24 jam
Lactulac 1x10 cc
Furosemid 3x1 IV
Spironolacton 3x100 PO
Curcuma 3x1 PO
Ranitidin 2x50 IV
Ceftriaxone 2x1 gram IV
PCT 5x1 tab PO
Ekstrak putih telur
22/12/14
IUVD Dextrose 5% 500cc / 24 jam
Lactulac 1x10 cc
Furosemid 3x1 IV
Spironolacton 3x100 PO
Curcuma 3x1 PO
Ranitidin 2x50 IV
Ceftriaxone 2x1 gram IV
Ekstrak putih telur
23/12/14
IUVD Dextrose 5% 500cc / 24 jam
Lactulac 1x10 cc
Furosemid 3x1 IV
Spironolacton 3x100 PO
Curcuma 3x1 PO
Ranitidin 2x50 IV
Ceftriaxone 2x1 gram IV
Ekstrak putih telur
25/12/14
IUVD Dextrose 5% 500cc / 24 jam
Lactulac 1x10 cc
Furosemid 3x1 IV
Spironolacton 3x100 PO
Curcuma 3x1 PO
Ranitidin 2x50 IV
Ceftriaxone 2x1 gram IV
Ekstrak putih telur
26/12/14
IUVD Dextrose 5% 500cc / 24 jam
Lactulac 1x10 cc
Furosemid 3x1 IV
Spironolacton 3x100 PO
Curcuma 3x1 PO
Ranitidin 2x50 IV
Ceftriaxone 2x1 gram IV
Ekstrak putih telur
27/12/14
Lactulac 1x10 cc
Furosemid 3x1 PO
Spironolacton 3x100 PO
Curcuma 3x1 PO
Ranitidin 2x1 PO
Ekstrak putih telur
1.7 PROGNOSIS
Ad Vitam : ad bonam
Ad Functionam : ad malam
Ad Sanationam : ad malam
1.8 RENCANA PENJAJAKAN
1. Pemeriksaan HBV DNA, HBeAg
2. Pemberian antivirus : Lamivudine 100 mg selama 48-52 minggu
3. Pemberian albumin 1,5 gram per kg IV dalam 6 jam, 1 gram per kg IV hari ke 3
4. Pengecekan ulang LFT
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 ANATOMI HATI
Hepar (hati) merupakan kelenjar yang terbesar dalam tubuh manusia. Hepar pada manusia terletak
pada bagian atas cavum abdominis, di bawah diafragma, di kedua sisi kuadran atas, yang sebagian besar
terdapat pada sebelah kanan. Beratnya 1200 – 1600 gram. Permukaan atas terletak bersentuhan di bawah
diafragma, permukaan bawah terletak bersentuhan di atas organ-organ abdomen. Hepar difiksasi secara erat
oleh tekanan intraabdominal dan dibungkus oleh peritoneum kecuali di daerah posterior-superior yang
berdekatan dengan vena cava inferior dan mengadakan kontak langsung dengan diafragma. Bagian yang
tidak diliputi oleh peritoneum disebut bare area. Terdapat refleksi peritoneum dari dinding abdomen
anterior, diafragma dan organ-organ abdomen ke hepar berupa ligamen. Macam-macam ligamen:
1. Ligamentum falciformis: Menghubungkan hepar ke dinding anterior abdomen dan
terletak di antara umbilicus dan diafragma.
2. Ligamentum teres hepatis/round ligament: Merupakan bagian bawah ligamentum
falciformis ; merupakan sisa-sisa peninggalan vena umbilicalis yg telah menetap.
3. Ligamentum gastrohepatica dan ligamentum hepatoduodenalis: Merupakan bagian
dari omentum minus yg terbentang dari curvatura minor lambung dan duodenum
sebelah prox ke hepar.Di dalam ligamentum ini terdapat arteri hepatika, vena porta
dan ductus choledocus communis. Ligamen hepatoduodenale turut membentuk tepi
anterior dari Foramen Wislow.
4. Ligamentum Coronaria Anterior ki–ka dan Lig coronaria posterior ki-ka:Merupakan
refleksi peritoneum terbentang dari diafragma ke hepar.
5. Ligamentum triangularis ki-ka: Merupakan fusi dari ligamentum coronaria anterior
dan posterior dan tepi lateral kiri kanan dari hepar.
Secara anatomis, organ hepar tereletak di hipochondrium kanan dan epigastrium,
dan melebar ke hipokondrium kiri. Hepar dikelilingi oleh cavum toraks dan bahkan pada
orang normal tidak dapat dipalpasi (bila teraba berarti ada pembesaran hepar). Permukaan
lobus kanan dpt mencapai sela iga 4/ 5 tepat di bawah aerola mammae. ligamentum
falciformis membagi hepar secara topografisbukan scr anatomis yaitu lobus kanan yang
besar dan lobus kiri.
Hepar memiliki dua sumber suplai darah, dari saluran cerna dan limpa melalui
vena porta hepatica dan dari aorta melalui arteri hepatika. Arteri hepatika keluar dari
aorta dan memberikan 80% darahnya kepada hepar, darah ini masuk ke hepar
membentuk jaringan kapiler dan setelah bertemu dengan kapiler vena akan keluar sebagai
vena hepatica. Vena hepatica mengembalikan darah dari hepar ke vena kava inferior.
Vena porta yang terbentuk dari vena lienalis dan vena mesenterika superior,
mengantarkan 20% darahnya ke hepar, darah ini mempunyai kejenuhan oksigen hanya
70 % sebab beberapa O2 telah diambil oleh limpa dan usus. Darah yang berasal dari vena
porta bersentuhan erat dengan sel hepar dan setiap lobulus dilewati oleh sebuah
pembuluh sinusoid atau kapiler hepatika.Pembuluh darah halus yang berjalan di antara
lobulus hepar disebut vena interlobular. Vena porta membawa darah yang kaya dengan
bahan makanan dari saluran cerna, dan arteri hepatika membawa darah yang kaya
oksigen dari sistem arteri. Arteri dan vena hepatika ini bercabang menjadi pembuluh-
pembuluh yang lebih kecil membentuk kapiler di antara sel-sel hepar yang membentik
lamina hepatika.Jaringan kapiler ini kemudian mengalir ke dalam vena kecil di bagian
tengah masing-masing lobulus, yang menyuplai vena hepatika. Pembuluh-pembuluh ini
menbawa darah dari kapiler portal dan darah yang mengalami deoksigenasi yang telah
dibawa ke hepar oleh arteri hepatika sebagai darah yang telah deoksigenasi.Selain vena
porta, juga ditemukan arteriol hepar didalam septum interlobularis. Anterior ini
menyuplai darah dari arteri ke jaringan jaringan septum diantara lobules yang berdekatan,
dan banyak arterior kecil mengalir langsung ke sinusoid hepar, paling sering pada
sepertiga jarak ke septum interlobularis.
Hepar terdiri atas bermacam-macam sel. Hepatosit meliputi 60% sel hepar,
sedangkan sisanya terdiri atas sel-sel epithelial sistem empedu dalam jumlah yang
bermakna dan sel-sel non parenkimal yang termasuk di dalamnya endothelium, sel
Kuppfer dan sel Stellata yang berbentuk seperti bintang.
Hepatosit sendiri dipisahkan oleh sinusoid yang tersusun melingkari eferen vena
hepatika dan ductus hepatikus. Saat darah memasuki hepar melalui arteri hepatica dan
vena porta menuju vena sentralis maka akan didapatkan pengurangan oksigen secara
bertahap. Sebagai konsekuensinya, akan didapatkan variasi penting kerentanan jaringan
terhadap kerusakan asinus. Membran hepatosit berhadapan langsung dengan sinusoid
yang mempunyai banyak mikrofili. Mikrofili juga tampak pada sisi lain sel yang
membatasi saluran empedu dan merupakan penunjuk tempat permulaan sekresi empedu.
Permukaan lateral hepatosit memiliki sambungan penghubungan dan desmosom yang
saling bertautan dengan disebelahnya.
Sinusoid hepar memiliki lapisan endothelial berpori yang dipisahkan dari
hepatosit oleh ruang Disse (ruang perisinusoidal). Sel-sel lain yang terdapat dalam
dinding sinusoid adalah sel fagositik Kuppfer yang merupakan bagian penting dalam
sistem retikuloendotelial dan sel Stellata (juga disebut sel Ito, liposit atau perisit) yang
memiliki aktivitas miofibriblastik yang dapat membantu pengaturan aliran darah
sinusoidal disamping sebagai faktor penting dalam perbaikan kerusakan hepar.
Peningkatan aktivitas sel-sel Stellata tampaknya menjadi faktor kunci pembentukan
fibrosis di hepar.
2. 2. FISIOLOGI HATI
Hati merupakan pusat dari metabolisme seluruh tubuh, merupakan sumber energi
tubuh sebanyak 20% serta menggunakan 20 – 25% oksigen darah. Ada beberapa fungsi
hati yaitu :
1. Fungsi hati sebagai metabolisme karbohidrat
Pembentukan, perubahan dan pemecahan KH, lemak dan protein saling berkaitan 1
sama lain.Hati mengubah pentosa dan heksosa yang diserap dari usus halus menjadi
glikogen, mekanisme ini disebut glikogenesis. Glikogen lalu ditimbun di dalam hati
kemudian hati akan memecahkan glikogen menjadi glukosa. Proses pemecahan
glikogen mjd glukosa disebut glikogenelisis.Karena proses-proses ini, hati merupakan
sumber utama glukosa dalam tubuh, selanjutnya hati mengubah glukosa melalui
heksosa monophosphat shunt dan terbentuklah pentosa. Pembentukan pentosa
mempunyai beberapa tujuan: menghasilkan energi, biosintesis dari nukleotida,
nucleic acid dan ATP, dan membentuk/ biosintesis senyawa 3 karbon (3C) yaitu
piruvic acid (asam piruvat diperlukan dalam siklus krebs).
2. Fungsi hati sebagai metabolisme lemak
Hati tidak hanya membentuk/mensintesis lemak tetapi sekaligus mengadakan
katabolisis asam lemak Asam lemak dipecah menjadi beberapa komponen :
1. Senyawa 4 karbon – Keton Bodies
2. Senyawa 2 karbon – Active Acetate (dipecah menjadi asam lemak dan gliserol)
3. Pembentukan cholesterol
4. Pembentukan dan pemecahan fosfolipid
Hati merupakan pembentukan utama, sintesis, esterifikasi dan ekskresi kolesterol,
dimana serum kolesterol menjadi standar pemeriksaan metabolisme lipid.
3. Fungsi hati sebagai metabolisme protein
Hati mensintesis banyak macam protein dari asam amino. dengan proses deaminasi,
hati juga mensintesis gula dari asam lemak dan asam amino. Dengan proses
transaminasi, hati memproduksi asam amino dari bahan-bahan non nitrogen. Hati
merupakan satu-satunya organ yg membentuk plasma albumin dan ∂-globulin dan
organ utama bagi produksi urea. Urea merupakan end product metabolisme protein. ∂
- globulin selain dibentuk di dalam hati, juga dibentuk di limpa dan sumsum tulang β
– globulin hanya dibentuk di dalam hati. Albumin mengandung ± 584 asam amino
dengan BM sekitar 66.000.
4. Fungsi hati sehubungan dengan pembekuan darah
Hati merupakan organ penting bagi sintesis protein-protein yang berkaitan dengan
koagulasi darah, misalnya membentuk fibrinogen, protrombin, faktor V, VII, IX, X.
Benda asing menusuk kena pembuluh darah – yang beraksi adalah faktor ekstrinsi,
bila ada hubungan dengan katup jantung – yang beraksi adalah faktor intrinsik. Fibrin
harus isomer biar kuat pembekuannya dan ditambah dengan faktor XIII, sedangakan
Vitamin K dibutuhkan untuk pembentukan protrombin dan beberapa faktor koagulasi.
5. Fungsi hati sebagai metabolisme vitamin
Semua vitamin disimpan di dalam hati khususnya vitamin A, D, E, dan K.
6. Fungsi hati sebagai detoksikasi
Hati adalah pusat detoksikasi tubuh, Proses detoksikasi terjadi pada proses oksidasi,
reduksi, metilasi, esterifikasi dan konjugasi terhadap berbagai macam bahan seperti
zat racun dan obat-obatan.
7. Fungsi hati sebagai fagositosis dan imunitas
Sel kupfer merupakan saringan penting bakteri, pigmen dan berbagai bahan melalui
proses fagositosis. Selain itu sel kupfer juga ikut memproduksi ∂-globulin sebagai
immune livers mechanism.
8. Fungsi hemodinamik
Hati menerima ± 25% dari cardiac output, aliran darah hati yang normal ± 1500 cc/
menit atau 1000 – 1800 cc/ menit. Darah yang mengalir di dalam a.hepatica ± 25%
dan di dalam v.porta 75% dari seluruh aliran darah ke hati. Aliran darah ke hepar
dipengaruhi oleh faktor mekanis, pengaruh persarafan dan hormonal, aliran ini
berubah cepat pada waktu berolahraga, terpapar terik matahari, dan syok. Hepar
merupakan organ penting untuk mempertahankan aliran darah.
2. 3. SIROSIS HEPATIS
2. 3. 1. DEFINISI
Istilah Sirosis hati diberikan oleh Laence tahun 1819, yang berasal dari kata
Khirros yang berarti kuning orange (orange yellow), karena perubahan warna pada nodul-
nodul yang terbentuk. Pengertian sirosis hati dapat dikatakan sebagai berikut yaitu suatu
keadaan disorganisasi yang difuse dari struktur hati yang normal akibat nodul regeneratif
yang dikelilingi jaringan mengalami fibrosis. Secara lengkap sirosis hati adalah
kemunduran fungsi liver yang permanen yang ditandai dengan perubahan histopatologi.
Yaitu kerusakan pada sel-sel hati yang merangsang proses peradangan dan perbaikan sel-
sel hati yang mati sehingga menyebabkan terbentuknya jaringan parut. Sel-sel hati yang
tidak mati beregenerasi untuk menggantikan sel-sel yang telah mati. Akibatnya, terbentuk
sekelompok-sekelompok sel-sel hati baru (regenerative nodules) dalam jaringan parut.
2. 3. 2. INSIDENS
Penderita sirosis hati lebih banyak dijumpai pada kaum laki-laki jika
dibandingkan dengan kaum wanita sekita 1,6 : 1 dengan umur rata-rata terbanyak antara
golongan umur 30 – 59 tahun dengan puncaknya sekitar 40 – 49 tahun.
2. 3. 3. ETIOLOGI
1. Alkohol
Alkhol adalah suatu penyebab yang paling umum dari cirrhosis, terutama didunia
barat. Perkembangan sirosis tergantung pada jumlah dan keteraturan dari
konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol pada tingkat-tingkat yang tinggi dan kronis
melukai sel-sel hati. Tiga puluh persen dari individu-individu yang meminum
setiap harinya paling sedikit 8 sampai 16 ounces minuman keras (hard liquor)
atau atau yang sama dengannya untuk 15 tahun atau lebih akan mengembangkan
sirosis. Alkohol menyebabkan suatu jajaran dari penyakit-penyakit hati; dari hati
berlemak yang sederhana dan tidak rumit (steatosis), ke hati berlemak yang lebih
serius dengan peradangan (steatohepatitis atau alcoholic hepatitis), ke sirosis.
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) merujuk pada suatu spektrum yang
lebar dari penyakit hati yang, seperti penyakit hati alkoholik (alcoholic liver
disease), mencakup dari steatosis sederhana (simple steatosis), ke nonalcoholic
Steatohepatitis (NASH), ke sirosis. Semua tingkatan-tingkatan dari NAFLD
mempunyai bersama-sama akumulasi lemak dalam sel-sel hati. Istilah
nonalkoholik digunakan karena NAFLD terjadi pada individu-individu yang tidak
mengkonsumsi jumlah-jumlah alkohol yang berlebihan, namun, dalam banyak
aspek-aspek, gambaran mikroskopik dari NAFLD adalah serupa dengan apa yang
dapat terlihat pada penyakit hati yang disebabkan oleh alkohol yang berlebihan.
NAFLD dikaitkan dengan suatu kondisi yang disebut resistensi insulin, yang pada
gilirannya dihubungkan dengan sindrom metabolisme dan diabetes mellitus tipe 2.
Kegemukan adalah penyebab yang paling penting dari resistensi insulin, sindrom
metabolisme, dan diabetes tipe 2. NAFLD adalah penyakit hati yang paling umum
di Amerika dan adalah bertanggung jawab untuk 24% dari semua penyakit hati.
2. Sirosis Kriptogenik,
Cryptogenic cirrhosis (sirosis yang disebabkan oleh penyebab-penyebab yang
tidak teridentifikasi) adalah suatu sebab yang umum untuk pencangkokan hati.
Di-istilahkan sirosis kriptogenik (cryptogenic cirrhosis) karena bertahun-tahun
para dokter telah tidak mampu untuk menerangkan mengapa sebagian dari pasien-
pasien mengembangkan sirosis. Dipercaya bahwa sirosis kriptogenik disebabkan
oleh NASH (nonalcoholic steatohepatitis) yang disebabkan oleh kegemukan,
diabetes tipe 2, dan resistensi insulin yang tetap bertahan lama. Lemak dalam hati
dari pasien-pasien dengan NASH diperkirakan menghilang dengan timbulnya
sirosis, dan ini telah membuatnya sulit untuk para dokter membuat hubungan
antara NASH dan sirosis kriptogenik untuk suatu waktu yang lama. Satu petunjuk
yang penting bahwa NASH menjurus pada sirosis kriptogenik adalah penemuan
dari suatu kejadian yang tinggi dari NASH pada hati-hati yang baru dari pasien-
pasien yang menjalankan pencangkokan hati untuk sirosis kriptogenik. Akhirnya,
suatu studi dari Perancis menyarankan bahwa pasien-pasien dengan NASH
mempunyai suatu risiko mengembangkan sirosis yang serupa seperti pasien-
pasien dengan infeksi virus hepatitis C yang tetap bertahan lama. Bagaimanapun,
kemajuan ke sirosis dari NASH diperkirakan lambat dan diagnosis dari sirosis
secara khas dibuat pada pasien-pasien pada umur kurang lebih 60 tahun.
3. Hepatitis Virus Yang Kronis
Hepatitis virus kronis adalah suatu kondisi dimana hepatitis B atau hepatitis C
virus menginfeksi hati bertahun-tahun. Kebanyakan pasien-pasien dengan
hepatitis virus tidak akan mengembangkan hepatitis kronis dan sirosis.
Contohnya, mayoritas dari pasien-pasien yang terinfeksi dengan hepatitis A
sembuh secara penuh dalam waktu berminggu-minggu, tanpa mengembangkan
infeksi yang kronis. Berlawanan dengannya, beberapa pasien-pasien yang
terinfeksi dengan virus hepatitis B dan kebanyakan pasien-pasien terinfeksi
dengan virus hepatitis C mengembangkan hepatitis yang kronis, yang pada
gilirannya menyebabkan kerusakan hati yang progresif dan menjurus pada sirosis,
dan ada kalanya kanker-kanker hati.
4. Kelainan-Kelainan Genetik Yang Diturunkan/Diwariskan
Berakibat pada akumulasi unsur-unsur beracun dalam hati yang menjurus pada
kerusakkan jaringan dan sirosis. Contoh-contoh termasuk akumulasi besi yang
abnormal (hemochromatosis) atau tembaga (penyakit Wilson). Pada
hemochromatosis, pasien-pasien mewarisi suatu kecenderungan untuk menyerap
suatu jumlah besi yang berlebihan dari makanan. Melalui waktu, akumulasi besi
pada organ-organ yang berbeda diseluruh tubuh menyebabkan sirosis, arthritis,
kerusakkan otot jantung yang menjurus pada gagal jantung, dan disfungsi
(kelainan fungsi) buah pelir yang menyebabkan kehilangan rangsangan seksual.
Perawatan ditujukan pada pencegahan kerusakkan pada organ-organ dengan
mengeluarkan besi dari tubuh melaui pengeluaran darah. Pada penyakit Wilson,
ada suatu kelainan yang diwariskan pada satu dari protein-protein yang
mengontrol tembaga dalam tubuh. Melalui waktu yang lama, tembaga
berakumulasi dalam hati, mata, dan otak. Sirosis, gemetaran, gangguan-gangguan
psikiatris (kejiwaan) dan kesulitan-kesulitan syaraf lainnya terjadi jika kondisi ini
tidak dirawat secara dini. Perawatan adalah dengan obat-obat oral yang
meningkatkan jumlah tembaga yang dieliminasi dari tubuh didalam urin.
5. Primary biliary cirrhosis (PBC)
PBC adalah suatu penyakit hati yang disebabkan oleh suatu kelainan dari sistim
imun yang ditemukan sebagian besar pada wanita-wanita. Kelainan imunitas pada
PBC menyebabkan peradangan dan perusakkan yang kronis dari pembuluh-
pembuluh kecil empedu dalam hati. Pembuluh-pembuluh empedu adalah jalan
dalam hati yang dilalui empedu menuju ke usus. Empedu adalah suatu cairan
yang dihasilkan oleh hati yang mengandung unsur-unsur yang diperlukan untuk
pencernaan dan penyerapan lemak dalam usus, dan juga campuran-campuran lain
yang adalah produk-produk sisa, seperti pigmen bilirubin. (Bilirubin dihasilkan
dengan mengurai/memecah hemoglobin dari sel-sel darah merah yang tua).
Bersama dengan kantong empedu, pembuluh-pembuluh empedu membuat saluran
empedu. Pada PBC, kerusakkan dari pembuluh-pembuluh kecil empedu
menghalangi aliran yang normal dari empedu kedalam usus. Ketika peradangan
terus menerus menghancurkan lebih banyak pembuluh-pembuluh empedu, ia juga
menyebar untuk menghancurkan sel-sel hati yang berdekatan. Ketika
penghancuran dari hepatocytes menerus, jaringan parut (fibrosis) terbentuk dan
menyebar keseluruh area kerusakkan. Efek-efek yang digabungkan dari
peradangan yang progresif, luka parut, dan efek-efek keracunan dari akumulasi
produk-produk sisa memuncak pada sirosis.
6. Primary Sclerosing Cholangitis (PSC)
PSC adalah suatu penyakit yang tidak umum yang seringkali ditemukan pada
pasien-pasien dengan radang usus besar. Pada PSC, pembuluh-pembuluh empedu
yang besar diluar hati menjadi meradang, menyempit, dan terhalangi. Rintangan
pada aliran empedu menjurus pada infeksi-infeksi pembuluh-pembuluh empedu
dan jaundice (kulit yang menguning) dan akhirnya menyebabkan sirosis. Pada
beberapa pasien-pasien, luka pada pembuluh-pembuluh empedu (biasanya sebagai
suatu akibat dari operasi) juga dapat menyebabkan rintangan dan sirosis pada hati.
7. Hepatitis Autoimun
Hepatitis autoimun adalah suatu penyakit hati yang disebabkan oleh suatu
kelainan sistim imun yang ditemukan lebih umum pada wanita-wanita. Aktivitas
imun yang abnromal pada hepatitis autoimun menyebabkan peradangan dan
penghancuran sel-sel hati (hepatocytes) yang progresif, menjurus akhirnya pada
sirosis.
8. Bayi-bayi dapat dilahirkan tanpa pembuluh-pembuluh empedu (biliary atresia)
dan akhirnya mengembangkan sirosis. Bayi-bayi lain dilahirkan dengan
kekurangan enzim-enzim vital untuk mengontrol gula-gula yang menjurus pada
akumulasi gula-gula dan sirosis. Pada kejadian-kejadian yang jarang,
ketidakhadiran dari suatu enzim spesifik dapat menyebabkan sirosis dan luka
parut pada paru (kekurangan alpha 1 antitrypsin).
9. Lain-lain
Penyebab-penyebab sirosis yang lebih tidak umum termasuk reaksi-reaksi yang
tidak umum pada beberapa obat-obat dan paparan yang lama pada racun-racun,
dan juga gagal jantung kronis (cardiac cirrhosis). Pada bagian-bagian tertentu dari
dunia (terutama Afrika bagian utara), infeksi hati dengan suatu parasit
(schistosomiasis) adalah penyebab yang paling umum dari penyakit hati dan
sirosis.
2. 3. 4. PATOFISIOLOGI
Darah vena dari lambung, pancreas, usus, limpa, dan kandung empedu berjalan
melalui vena porta menuju hati. Di dalam sinusoid, darah tersebut akan bercampur
dengan darah kaya oksigen dari arteri hepatica, untuk selanjutnya berhubungan erat
dengan hepatosit. Sekitar 15% curah jantung akan mengalir ke hati, tetapi resistensi
alirannya sangat rendah sehingga tekanan vena porta normal 4-8 mmHg. Jika daerah
potongan melintang di jalinan pembuluh darah hati terbatas, tekanan vena porta
meningkat dan terjadi hipertensi portal. Penyebabnya dapat berupa peningkatan resistensi
pembuluh darah berikut, meskipun perbedaan yang jelas dari ketiga bentuk obstruksi
intrahepatik tidak selamanya ada atau memungkinkan :
Prahepatik: Trombosis vena porta
Pascahepatik: Gagal jantung kanan, perikarditis konstriktif, dll
Intrahepatik:
Prasinusoid: Hepatitis kronis, sirosis bilier primer, granuloma pada
sistomiasis, tuberculosis, leukemia, dll
Sinusoid : Hepatitis akut, kerusakan akibat alcohol (perlemakan hati,
sirosis), toksin, amiloidosis
Pascasinusoid : Penyakit oklusi vena pada vena kecil dari venula, sindrom
Bud-Chiari (obstruksi vena hepatica besar)
Pembesaran hepatosit (penimbunan lemak, pembengkakan sel, hyperplasia) dan
peningkatan pembentukan matriks ekstrasel mempermudah terjadinya obstruksi sinusoid.
Karena matriks ekstrasel juga mengganggu pertukaran zat dan gas antara sinusoid dan
hepatosit, pembengkakan sel akan semakin meningkat. Penimbunan amiloid dapat
memiliki efek obstruksi sama. Akhirnya, pada hepatitis akut dan nekrosis hati akut,
ruangan sinusoid dapat tersumbat oleh debris sel. Akibat dari hipertensi portal.
Dimanapun tempat obstruksinya, peningkatan tekanan vena portal akan menyebabkan
gangguan di organ sebelumnya (malabsorbsi, splenomegali, dengan anemia, dan
trombositopenia) serta aliran darah dari organ abdomen melalui saluran pembuluh darah
yang melewati hati. Sirkuit yang melewati portal ini menggunakan pembuluh darah
kolateral yang normalnya berdinding tipis, namun kemudian menjadi sangat membesar
(pembentukan varises: “hemoroid” pleksus vena rectum; caput medusa di vena
paraumbilikalis). Pembesaran vena esophagus terutama menimbulkan bahaya ruptur.
Vasodilator yang dilepaskan pada hipertensi portal (glucagon, VIP, substansi P,
prostasiklin, NO, dll) juga mengakibatkan turunnya tekanan darah sistemik. Hal ini
meningkatkan curah jantung kompensasi sehingga menyebabkan hiperperfusi di organ
abdomen dan sirkuit kolateral. Kerusakan hati dapat menyebabkan obstruksi sinusoid,
pascasinusoid, dan pascahepatik. Akibatnya, drainase limfe hepatic yang kaya protein
menjadi terganggu dan tekanan portal meningkat, kadang-kadang bersama dengan
penurunan tekanan osmotic plasma karena kerusakan hati (hipoalbuminemia), sehingga
menekan cairan yang kaya protein ke dalam rongga abdomen, yakni cairan ascites. Hal
tersebut menyebabkan hiperaldosteronisme sekunder yang mengakibatkan peningkatan
volume ekstrasel. Karena darah yang dibuang melewati hati dari usus mengandung zat
toksik (NH3, aminbiogenik, asam lemak rantai pendek, dll) yang normalnya dibuang dari
darah portal melalui sel hati diantaranya akan mencapai SSP sehingga terjadi ensefalopati
portal sistemik.
Sirosis hati adalah penyakit dengan proses nekrosis, inflamasi, fibrosis, regenerasi
nodular, dan pembentukan anastomosis vaskular yang kurang lebih terjadi secara
bersamaan. Biasanya disebabkan oleh efek jangka panjang dari faktor yang berbahaya,
terutama penyalahgunaan alkohol yang merupakan penyebab dari 50% kasus di seluruh
dunia. Kemungkinan terjadinya sirosis setelah mengkonsumsi 13 kg etanol/kgBB secara
kumulatif. Zat yang paling berperan dalam pembentukan fibrosis dan sirosis adalah
metabolit etanol berupa asetaldehid. Sirosis juga merupakan stadium akhir dari virus
hepatitis. Pada penyakit fluminan akut, sirosis dapat terjadi dalam beberapa minggu; pada
penyakit kronis rekuren dapat terjadi setelah berbulan-bulan maupun bertahun-tahun.
Faktor yang terlibat dalam kerusakan sel hati adalah :
Defisiensi ATP akibat gangguan metabolisme energi sel
Peningkatan pembentukan metabolit oksigen yang sangat reaktif (O2-, HO2, H202)
Defisiensi antioksidan (misal : glutation) dan/ atau kerusakan enzim perlindungan
(glutation peroksidase, superoksida dismutase) yang timbul bersamaan
Metabolit O2 misalnya akan bereaksi dengan asam lemak tidak jenuh pada fosfolipid
(peroksidase lemak). Hal ini membantu terjadinya kerusakan membran plasma dan
organel sel (lisosom, retikulum endoplasma). Akibatnya, konsentrasi Ca2+ di sitosol
meningkat, yang mengaktifkan protease dan enzim lain sehingga akhirnya terjadi
kerusakan sel yang bersifat ireversibel. Fibrosis hati terjadi dalam beberapa tahap. Jika
hepatosist yang rusak mati, diantaranya akan terjadi kebocoran enzim lisosom dan
pelepasan sitokin dari matriks ekstrasel. Sitokin ini bersama dengan debris sel yang mati
akan mengaktifkan sel Kupffer dan sel inflamasi yang terlibat. Faktor pertumbuhan ini
dan sitokin selanjutnya mengubah sel Ito penyimpan lemak di hati menjadi miofibroblas,
mengubah monosit yang bermigrasi menjadi makrofag aktif, memicu proliferasi
fibroblas. Aksi kemotaktik TGF-β dan protein kemotaktik monosit 1 (MCP-1), yang
dilepaskan dari sel ito (dirangsang oleh TNF-α, Platelete Derived Growth Factor/PDGF,
dan interleukin yang memperkuat proses ini demikian pula dengan sejumlah zat sinyal
lainnya. Akibat sejumlah reaksi ini, pembentukan matriks ekstrasel ditingkatkan oleh
fibroblas dan miofibroblas, berarti menyebabkan peningkatan penimbunan kolagen,
proteoglikan, dan glikoprotein di ruang Disse. Fibrosis glikoprotein diruang Disse
menghambat pertukaran zat antara sinusoid darah dan hepatosit, serta meningkatkan
resistensi aliran sinusoid. Jumlah matriks yang berlebihan dapat dirusak oleh mula-mula
leh metaloprotease, dan hepatosit akan mengalami regenerasi. Jika nekrosis terbatas pada
pusat lobulus hati, penggunaan struktur hati yang sempurna dimungkinkan terjadi.
Namun, jika nekrosis telah meluas menembus parenkim perifer lobulus hati, akan
terbentuk septa jaringan ikat. Akibatnya regenerasi fungsional yangs sempurna tidak
mungkin lagi terjadi dan akan terbentuk nodul.
2. 3. 5. KLASIFIKASI
A. Berdasarkan morfologi Sherlock membagi Sirosis hati atas 3 jenis, yaitu :
1. Mikronodular
Ditandai dengan terbentuknya septa tebal teratur, di dalam septa parenkim hati
mengandung nodul halus dan kecil yang merata. Sirosis mikronodular besar
nodulnya sampai 3 mm, sedangkan sirosis makronodular ada yang berubah
menjadi makronodular sehingga dijumpai campuran mikro dan makronodular.
2. Makronodular
Sirosis makronodular ditandai dengan terbentuknya septa dengan ketebalan
bervariasi, mengandung nodul yang besarnya juga bervariasi ada nodul besar
didalamnya ada daerah luas dengan parenkim yang masih baik atau terjadi
regenerasi parenkim.
3. Campuran (yang memperlihatkan gambaran mikro-dan makronodular)
B. Secara Fungsional Sirosis terbagi atas :
1. Sirosis hati kompensata. Sering disebut dengan Laten Sirosis hati. Pada stadium
kompensata ini belum terlihat gejala-gejala yang nyata. Biasanya stadium ini
ditemukan pada saat pemeriksaan screening.
2. Sirosis hati Dekompensata Dikenal dengan Active Sirosis hati, dan stadium ini
Biasanya gejala-gejala sudah jelas, misalnya : ascites, edema dan ikterus. Sesuai
dengan konsensus Baveno IV, sirosis hepatis dapat diklasifikasikan menjadi
empat stadium klinis berdasarkan ada tidaknya varises, ascites, dan perdarahan
varises, yaitu:
a. Stadium 1 : tidak ada varises, tidak ada ascites
b. Stadium 2 : varises tanpa ascites
c. Stadium 3 : ascites dengan atau tanpa varises
d. Stadium 4 : perdarahan dengan atau tanpa ascites
Stadium 1 dan 2 dikategorikan sebagai kelompok sirosis kompensata, sementara
stadium 3 dan 4 dalam kelompok sirosis dekompensata.
2. 3. 6. MANIFESTASI KLINIS
Gejala yang timbul tergantung pada tingkat berat sirosis hati yang terjadi. Sirosis
Hati dibagi dalam tiga tingkatan yakni Sirosis Hati yang paling rendah Child A, Child B,
hingga pada sirosis hati yang paling berat yakni Child C. Gejala yang biasa dialami
penderita sirosis dari yang paling ringan yakni lemah tidak nafsu makan, hingga yang
paling berat yakni bengkak pada perut, tungkai, dan penurunan kesadaran. Pada
pemeriksaan fisik pada tubuh penderita terdapat palmar eritem, spider nevi seperti
gambar dibawah ini.
Beberapa dari gejala-gejala dan tanda-tanda sirosis yang lebih umum termasuk:
1. Spider angioma atau spider nervi
2. Palmar eritema
3. Perubahan kuku (Muehrche’s lines, Terry lines, Clubbing)
4. Osteoartropati hipertrofi
5. Kontraktur Duputeyrn
6. Ginekomastia
7. Hipoganadisme
8. Ukuran hati: Besar, normal, mengecil
9. Splenomegali
10. Ascites
11. Caput medusa
12. Mur-mur Cuveihier Baungarten
13. Fetor hepaticus
14. Ikterus
15. Asterixis/Flapping tremor
Pada keadaan sirosis hati lanjut, terjadi pemecahan protein otot. Asam amino
rantai cabang (AARC) yang terdiri dari valin, leusin, dan isoleusin digunakan sebagai
sumber energi (kompensasi gangguan glukosa sebagai sumber energi) dan untuk
metabolisme amonia. Dalam hal ini, otot rangka berperan sebagai organ hati kedua
sehingga disarankan penderita sirosis hati mempunyai massa otot yang baik dan bertubuh
agak gemuk. Dengan demikian, diharapkan cadangan energi lebih banyak, stadium
kompensata dapat dipertahankan, dan penderita tidak mudah jatuh pada keadaan koma.
Penderita sirosis hati harus meringankan beban kerja hati. Aktivitas sehari-hari
disesuaikan dengan kondisi tubuh. Pemberian obat-obatan (hepatotoksik) harus dilakukan
dengan sangat hati-hati. Penderita harus melakukan diet seimbang, cukup kalori, dan
mencegah konstipasi. Pada keadaan tertentu, misalnya, asites perlu diet rendah protein
dan rendah garam.
2. 3. 7. KOMPLIKASI
1. Ascites
Penyebab ascites yang paling banyak pada SH adalah HP, disamping adanya
hipoalbuminemia, dan disfungsi ginjal yang akan mengakibatkan akumulasi cairan ke
peritoneum.
2. Spontaneous Bacterial Peritonitis (SBP)
Peritonitis bacterial spontan merupakan komplikasi berat dan sering terjadi pada
ascites yang ditandai dengan infeksi spontan ascites tanpa disertai focus infeksi
intraabdominal. Escherichia coli merupakan salah satu bakteri usus yang paling
sering menyebabkan SBP. Diagnosis SBP ditegakkan bila pada sampel cairan asites
ditemukan neutrofil >250/mm2.
3. Varises esofagus
Pada sirosis hati, jaringan parut menghalangi aliran darah yang kembali ke jantung
dari usus-usus dan meningkatkan tekanan dalam vena portal (hipertensi portal).
Ketika tekanan dalam vena portal menjadi cukup tinggi, ia menyebabkan darah
mengalir di sekitar hati melalui vena-vena dengan tekanan yang lebih rendah untuk
mencapai jantung. Vena-vena yang paling umum yang dilalui darah untuk
membypass hati adalah vena-vena yang melapisi bagian bawah dari kerongkongan
(esophagus) dan bagian atas dari lambung. Sebagai suatu akibat dari aliran darah
yang meningkat dan peningkatan tekanan yang diakibatkannya, vena-vena pada
kerongkongan yang lebih bawah dan lambung bagian atas mengembang dan mereka
dirujuk sebagai esophageal dan gastric varices; lebih tinggi tekanan portal, lebih besar
varices-varices dan lebih mungkin seorang pasien mendapat perdarahan dari varices-
varices kedalam kerongkongan (esophagus) atau lambung. Perdarahan juga mungkin
terjadi dari varices-varices yang terbentuk dimana saja didalam usus-usus, contohnya,
usus besar (kolon), namun ini adalah jarang.Untuk sebab-sebab yang belum
diketahui, pasien-pasien yang diopname karena perdarahan yang secara aktif dari
varices-varices kerongkongan mempunyai suatu risiko yang tinggi mengembangkan
spontaneous bacterial peritonitis.
4. Ensefalopati hepatikum
Mekanisme terjadinya ensefalopati hepatikum adalah akibat hiperamonia, terjadi
penurunan uptake hapatik akibat HP dan atau penurunan sintesis urea dan glutamik.
5. Sindrom hepatorenal
Sindrom ini adalah suatu komplikasi yang serius dimana fungsi dari ginjal-ginjal
berkurang. Hal tersebut adalah suatu persoalan fungsi dalam ginjal-ginjal, yaitu, tidak
ada kerusakn fisik pada ginjal.Sindroma hepatorenal tipe 1 ditandai dengan gangguan
progresif fungsi ginjal dan penurunan kliren kreatinin secara bermakna dalam 1-2
minggu. Tipe 2 ditandai dengan penurunan filtrasi glomerulus dengan peningkatan
serum kreatinin.
6. Splenomegali
Limpa (spleen) secara normal bertindak sebagai suatu saringan (filter) untuk
mengeluarkan/menghilangkan sel-sel darah merah, sel-sel darah putih, dan platelet-
platelet (partikel-partikel kecil yang penting uktuk pembekuan darah) yang lebih tua.
Darah yang mengalir dari limpa bergabung dengan darah dalam vena portal dari usus-
usus. Ketika tekanan dalam vena portal naik pada sirosis, ia bertambah menghalangi
aliran darah dari limpa. Darah tersendat dan berakumulasi dalam limpa, dan limpa
membengkak dalam ukurannya, suatu kondisi yang dirujuk sebagai splenomegali.
Ketika limpa membesar, ia menyaring keluar lebih banyak dan lebih banyak sel-sel
darah dan platelet-platelet hingga jumlah-jumlah mereka dalam darah berkurang.
7. Kanker Hati
II. 3. 8. DIAGNOSTIK DAN PENATALAKSANAAN
A. Pemeriksaan Diagnostik
a. Scan/biopsy hati : Mendeteksi infiltrate lemak, fibrosis, kerusakan
jaringan hati,
b. USG : Ekodensitas hati meningkat dengan ekostruktur kasar homogen
atau heterogen pada sisi superficial, sedang pada sisi profunda ekodensitas
menurun. Ascites tampak sebagai area bebas gema (ekolusen) antara organ
intra abdominal dengan dinding abdomen.
c. CT Scan, MRI : Menilai derajat berat SH dengan menilai ukuran lien,
ascites, dan kolateral vaskular.
d. Kolesistografi/kolangiografi : Memperlihatkan penyakit duktus empedu
yang mungkin sebagai faktor predisposisi.
e. Esofagoskopi : Dapat melihat adanya varises esophagus
f. Portografi Transhepatik perkutaneus : Memperlihatkan sirkulasi system
vena portal
B. Pemeriksaan laboratorium
- ALT, AST, ALP, Γgt, bilirubin, albumin, globulin, PT, natrium, trombosit,
lekosit dan neutrofil, anemia makrositik, mikrositik, normokrom).
- Serologi virus hepatitis, auto antibodi untuk autoimun hepatitis (ANA, ASM,
Anti-LKM), saturasi transferin dan feritin untuk hemokromatosis, ceruloplasmin
dan cooper untuk penyakit wilson, alpha 1-antitrypsin, AMA untuk sirosis bilier
primer, antibodi ANCA untuk kolangitis sklerosis primer.
C. Penatalaksanaan
Pengobatan sirosis hati pada prinsipnya berupa :
1. Simtomatis
2. Pengobatan yang spesifik dari sirosis hati akan diberikan jika telah terjadi
komplikasi seperti :
1) Asites
2) Spontaneous bacterial peritonitis
3) Hepatorenal syndrome
4) Ensefalophaty hepatic
1. Asites
Dikendalikan dengan terapi konservatif yang terdiri atas :
- istirahat
- diet rendah garam : untuk asites ringan dicoba dulu dengan istirahat dan diet rendah
garam berupa 5,2 gram atau 90 mmol/hari.
- Diuretik
Pemberian diuretik hanya bagi penderita yang telah menjalani diet rendah garam dan
pembatasan cairan namun penurunan berat badannya kurang dari 1 kg setelah 4 hari.
Mengingat salah satu komplikasi akibat pemberian diuretic adalah hipokalemia dan hal
ini dapat mencetuskan encephalopaty hepatic, maka pilihan utama diuretic adalah
spironolacton, dan dimulai dengan dosis rendah, 100-200 mg sekali sehari maks 400 mg,
apabila dengan dosis maksimal diuresinya belum tercapai maka dapat kita kombinasikan
dengan furosemid 20-40 mg/hari, maksimal 160 mg/hari. Parasintesis jika ascites
mencapai 4-6 liter dan dilindungi pemberian albumin, 8-10 gram IV per liter cairan
parasisntesis (jika >5L), restriksi cairan jika Natrium serum <120-125 mmol/L.
2. Spontaneous bacterial peritonitis
Pengobatan SBP dengan memberikan Cephalosporins Generasi III (Cefotaxime), secara
parental selama lima hari, dan albumin 2 gram IV tiap 8 jam atau 1,5 gram per kg IV
selama 6 jam, 1 gram per kg IV hari ke 3. Mengingat akan rekurennya tinggi maka untuk
Profilaxis dapat diberikan Norfloxacin (400mg/hari) oral 2x/hari untuk terapi, 400 mg
oral 2x/hari selama 7 hari untuk perdarahan GIT, 400 mg oral per hari untuk profilaksis,
Trimethroprim/sulfamethoxazole 1 tablet oral/hari untuk profilaksis, 1 tablet oral 2x/hari
untuk perdarahan GIT.
3. Hepatorenal Syndrome
Transjuguar intrahepatic portosystemic shunt efektif menurunkan hipertensi porta dan
memperbaiki HRS, serta menurunkan perdarahan GIT. Bila terapi medis gagal
dipertimbangkan transplantasi hati merupakan terapi definitif.
4. Perdarahan karena pecahnya Varises Esofagus
Kasus ini merupakan kasus emergensi sehingga penentuan etiologi sering
dinorduakan, namun yang paling penting adalah penanganannya lebih dulu. Prinsip
penanganan yang utama adalah tindakan Resusitasi sampai keadaan pasien stabil,
dalam keadaan ini maka dilakukan :
Pasien diistirahatkan dan dipuasakan
Pemasangan IVFD berupa garam fisiologis dan kalau perlu transfusi
Pemberian obat-obatan berupa propanolol 40-80 mg oral 2x/hari, isosorbid
mononitrat 2 mg oral 2x/hari, saat perdaran akut diberikan somatostatin atau
oktreotid diteruskan skleroterapi atau ligasi endoskopi
5. Ensefalopati Hepatikum
Pemberian laktulosa 30-45 mL sirup oral 3-4x/hari atau 300 mL enema sampai 2-4x
BAB/hari dan perbaikan status mental dan neomisin 4-12 gram oral/hari dibagi tiap 6-8
jam, dapat ditambahkan pada pasien yang refrakter laktulosa
3. 3.9. PROGNOSIS
Skor/parameter 1 2 3
Bilirubin(mg %) < 2,0 2 - < 3 > 3,0
Albumin(mg %) > 3,5 2,8 - < 3,5 < 2,8
Protrombin time
( Quick %)
> 70 40 - < 70 < 40
Asites 0 Min. – sedang
(+) – (++)
Banyak (+++)
Hepatic
Encephalopathy
Tidak ada Stadium 1 & 2 Stadium 3 & 4
Klasifikasi sirosis hati menurut Child – Pugh :
Skor Child-Pugh atau sering disebut juga skor Child-Turcotte-Pugh digunakan untuk
menilai prognosis pasien dengan penyakit hepar kronik terutama sirosis hepatis.
Meskipun pada awalnya skor ini hanya digunakan untuk memprediksi mortalitas pasien
selama menjalani pembedahan, saat ini skor ChildPugh digunakan untuk menilai
prognosis yang diperlukan untuk transplantasi hepar serta staging secara klinis pada
sirosis hepatis.
Skor Child-
Pugh A
menunjukkan
sirosis hepatis
kompensata,
sedangkan B
menunjukkan
sirosis hepatis dekompensata.
Variabel-variabel yang digunakan untuk perhitungan skor Child-Pugh bukan spesifik
marker untuk menggambarkan fungsi sintesis dan eliminasi hepar. Perubahan serum
albumin dapat menunjukkan peningkatan permeabilitas vaskuler karena sepsis dan
ascites. Demikian juga peningkatan bilirubin dapat disebabkan oleh kegagalan fungsi
ginjal, proses hemolisis, atau sepsis. Akan tetapi, secara umum, skor Child-Pugh dapat
menilai kondisi umum pasien sirosis dan menilai perubahan multiorgan yang disebabkan
oleh sirosis hepatis. Penelitian-penelitian sebelumnya membuktikan bahwa skor Child-
Pugh dapat digunakan sebagai perangkat prognostik pada kejadian ascites, rupture varises
esofagus, sirosis alkoholik, sirosis hepatis terkait hepatitis C, sirosis biliaris primer,
primary sclerosing cholangitis, dan sindrom Budd-Chiari. Oleh karena kelima variabel
yang digunakan dalam skor Child-Pugh dipilih secara empiris, maka tidak semua variabel
tersebut merupakan variabel independen terhadap prediksi prognosis. Nilai cut-off untuk
tiap variabel juga ditetapkan secara empiris sehingga belum dapat mencakup semua
kemungkinan.
BAB III
KESIMPULAN
Mengingat pengobatan sirosis hati hanya merupakan simptomatik dan mengobati
penyulit, maka prognosa Sirosis Hepatis bisa buruk. Umumnya menegakkan diagnosis
diperlukan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan laboratorium terhadap sirosis hepatis
tersebut. Namun penemuan sirosis hati yang masih terkompensasi mempunyai prognosa
yang baik. Oleh karena itu ketepatan diagnosa dan penanganan yang tepat sangat
dibutuhkan dalam penatalaksanaan sirosis hati.
DAFTAR PUSTAKA
1. Sutadi SM. Sirosis hati. Usu repository. 2003. [cited on 2014 December 24th].
Available from : URL : http:// repository.usu.ac.id/ bitstream/ 123456789 /3386/1/
penydalam-srimaryani5.pdf
2. Suyono,Sufiana,Heru,Novianto,Riza,Musrifah. Sonografi sirosis hepatis di RSUD
Dr. Moewardi. Kalbe. 2006. [cited on 2011 2014 December 24th]. Available
from : URL
http://www.kalbe.co.id/files/cdk/files/09_150_Sonografisirosishepatis.pdf/
09_150_Sonografisirosishepatis.html
3. Raymon T.Chung, Daniel K.Podolsky. Cirrhosis and its complications. In :
Kasper DL et.al, eds. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 16 th Edition.
USA : Mc-Graw Hill; 2005. p. 1858-62.
4. Nurdjanah Sitti. Sirosis hati. Dalam : Sudoyo AW et.al, eds. Buku Ajar Ilmu
Penyakit Dalam. Edisi 4. Jakarta : Pusat Penerbitan ilmu Penyakit Dalam Fakultas
Kedokteran UI; 2006. hal. 443-53.
5. Amiruddin Rifai. Fisiologi dan Biokimia Hati. Dalam : Sudoyo AW et.al, eds.
Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Edisi 4. Jakarta : Pusat Penerbitan ilmu Penyakit
Dalam Fakultas Kedokteran UI; 2006. hal. 415-6.
6. Faiz O, Moffat D. The liver, gall-bladder, biliary tree. In : Anatomy at a glance.
USA: Blackwell Publishing Company; 2002. p. 44-5.
7. Lindseth, Glenda N. Gangguan Hati, Kandung Empedu, dan Pankreas. Dalam :
Sylvia A.Price et.al, eds. Patofisiologi. Edisi 6. Jakarta : Penerbit Buku
Kedokteran EGC ; 2006. Hal.472-5.
8. Netter FH. Surface and bed of liver. In : Atlas of Human Anatomy. 4 th Edition.
USA : Saunders Elsevier; 2006. p. 287.
9. Douglas Eder. Histology. In : Laboratory Atlas of Anatomy and Physiology. 4 th
Edition. USA : McGraw-Hill Science; 2001. p.35
10. Hall & Guyton. Fisiologi Kedokteran. Edisi 11. Jakarta : Penerbit Buku
Kedokteran EGC; 2004. hal. 902-6.
11. Kumar V, Cotran RS, Robbins SL. Hati dan saluran empedu Dalam : Hartanto H,
Darmaniah N, Wulandari N. Robbins Buku Ajar Patologi. 7 th Edition. Volume 2.
Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC; 2004. hal. 671-2.
12. Taylor CR. Cirrhosis. emedicine. 2009. [cited on 2014 December 24th]. Available
from: URL : http://emedicine.medscape.com/article/366426-overview