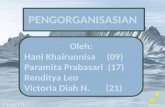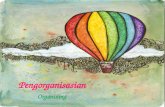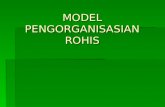Karakter pengorganisasian diri petani Indonesia
-
Upload
syahyuti-si-buyuang -
Category
Science
-
view
22 -
download
4
Transcript of Karakter pengorganisasian diri petani Indonesia

129
PENGORGANISASIAN SECARA PERSONAL DAN GEJALA INDIVIDUALISASI ORGANISASI SEBAGAI KARAKTER UTAMAPENGORGANISASIAN DIRI PETANI DI INDONESIA Syahyuti
PENGORGANISASIAN SECARA PERSONAL DAN GEJALA INDIVIDUALISASIORGANISASI SEBAGAI KARAKTER UTAMA PENGORGANISASIAN DIRI
PETANI DI INDONESIA
Personalized Organizing and Invidualized Organization Symptoms as The MainCharacters of Farmers’ Organization in Indonesia
Syahyuti
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan PertanianJl. A. Yani No. 70 Bogor 16161Email: [email protected]
Naskah masuk : 6 Agustus 2012 Naskah diterima : 18 Oktober 2012
ABSTRACT
Explaining how farmers conduct their farm business is trapped in organization theory and analysis, sofar. This paper applies concept and theory of new institutionalism understanding which focuses social relation asthe most basic object of analysis. It is found that farmers’ organizations in Indonesia are unique indicated byorganization individualization as the real fact of formal farmers’ organization. This symptom is not observed if itemploys organization analysis. It comes from the previous farmers’ organizations before the formal organization isacknowledged, namely personalized organizing. These two findings are based on recognizing that farmers arerational, creative social actors using all institution and organization resources for running their farm business. Inthe future, empowering farmers is carried out through offering other types than formal organization for moreeffective social relation.
Key words: institution, institutionalism, organization, self-organizing, personalized organizing, individualizedorganization, farmers
ABSTRAK
Penjelasan tentang bagaimana petani menjalankan usaha pertaniannya selama ini terperangkap hanyapada teori dan analisis organisasi. Berbeda dengan ini, tulisan berikut menggunakan konsep dan teori daripemahaman Kelembagaan Baru (New Institutionalism), dengan menjadikan relasi sosial (social relation) sebagaiobjek yang paling pokok dan elementer dalam analisisnya. Melalui paham ini ditemukan pola pengorganisasianyang khas pada petani di Indonesia saat ini yakni gejala “individualisasi organisasi” yang merupakan faktasesungguhnya dalam organisasi-organisasi formal milik petani. Gejala ini tidak terlihat jika menggunakan analisisorganisasi. Sesungguhnya bentuk ini berakar dari pola pengorganisasian diri petani dahulu sebelum dikenalorganisasi formal, yakni “pengorganisasian secara personal”. Kedua temuan ini muncul dengan menggunakanbasis pemahaman bahwa petani adalah aktor sosial yang rasional-kreatif yang menggunakan berbagaisumberdaya lembaga dan organisasi sebagai modal dalam menjalankan usahanya. Ke depan, pemberdayaanpetani semestinya memberi peluang kepada bentuk-bentuk lain selain organisasi formal, karena relasi sosialyang efektif tidak hanya berlangsung dalam organisasi formal.
Kata kunci : lembaga, kelembagaan, organisasi, pengorganisasian diri, pengorganisasian secara personal,individualisasi organisasi, petani

130
FORUM PENELITIAN AGRO EKONOMI, Volume 30 No. 2, Desember 2012 : 129 -145
PENDAHULUAN
Teori dan praktek pemberdayaanselama ini terbatas hanya pada pendekatanorganisasi formal, baik pada kalanganpemerintah, Non Organization Organization(NGO), maupun kalangan akademisi.Mengelompokkan peserta program dipandangsebagai strategi yang paling tepat. Paham iniditurunkan dari literatur di perguruan tinggiyang mengembangkannya dari studi-studiterhadap masyarakat yang tergolong berhasilyang menjalankan kegiatannya dalamorganisasi formal. Teori-teori pemberdayaanditurunkan dari teori organisasi, yangdikembangkan dari kasus-kasus yang berhasilbelaka, dengan latar belakang padamasyarakat industri atau masyarakat petanipedesaan yang hidup di negara maju.Meskipun cukup banyak yang memaparkanorganisasi petani, namun yang diangkatadalah organisasi petani di negara maju yangsangat berbeda latar belakangnya dengan diIndonesia. Sementara, penelitian tentangorganisasi petani di negara berkembang yangkondisinya serupa terbatas hanya pada kasusyang berhasil (success story) saja.
Akibatnya, kegiatan pemberdayaandengan berbasiskan teori tersebut mencapaihasil yang mengecewakan. Dalamkenyataannya, kelompok-kelompok dalamkegiatan pemberdayaan tersebut tidakberkembang sesuai harapan, sehingga tidakmampu mendukung pencapaian tujuanprogram. Di negara berkembang umumnya,sangat jarang petani berada dalam organisasiformal, dan jika pun ada kapasitaskeorganisasian mereka sangat lemah(Bourgeois et al., 2003). Kondisi ini relatifserupa di banyak belahan dunia lain (Grootaertdan Bastelaer, 2001). Tidak mudahmembangun organisasi petani (Hellin et al.,2007), karena petani cenderung merasa lebihbaik tidak berorgansiasi (Stockbridge et al.,2003).
Akar masalahnya adalah karenapenggunaan keilmuan yang basisnya kurangsesuai namun juga kaku pada diri pengambilkebijakan dalam memandang masyarakatdesa (lihat misalnya Chambers, 1987;Nordholt, 1987; Pakpahan, 2004). Padahalsecara sosiologis, dalam setiap relasi petani
memiliki dua pilihan yaitu relasi yang bersifatindividual dan relasi dalam bentuk aksi kolektif.Relasi kolektif bisa dalam organisasi formalmaupun non formal. Namun, dalam ilmupemberdayaan selama ini dibatasi hanyaberupa organisasi formal, sebagaimanamudah ditelusuri pada berbagai literaturmaupun produk kebijakan pemerintah.Pendekatan ini tidak mengakui rasionalitaspetani.
Tulisan ini berupaya membongkarkerangka pengetahuan ini denganmenggunakan pendekatan pahamkelembagaan baru (new institutionalism)terutama dari pemikiran Scott (2008), yangmerupakan perkembangan terakhir dari ilmukelembagaan saat ini. Titik masuk dalamtulisan ini adalah konsep “pengorganisasiandiri petani”, yakni bagaimana petani menjalinrelasi dengan berbagai pihak dalammenjalankan usaha pertanian di pedesaanselama ini. Pengorganisasian dimaksudditelaah dengan teori ”lembaga” (institutions)dan ”organisasi” (organization). Kedua konsepini dinilai paling dekat serta juga cukup kuatkaitannya untuk menjelaskan fenomena ini.Penelaahan harus masuk pada bagian yangpaling elementer yakni individu dan relasi-relasi yang terbangun. Organisasi hanyalahsalah satu bentuk dari sekumpulan relasi.Kelemahan analisis selama ini adalah karenaberbasiskan kepada “organisasi”, padahalorganisasi hanyalah salah satu model jejaringrelasi sosial.
Tulisan ini merupakan review darikajian teoritis dan praktek yang berasal dariberbagai sumber. Narasi diawali denganpenjelasan konsep, lalu dilanjutkan pemaparantentang pengorganisasian diri petani dari dulusampai sekarang, dan diakhiri dengan suatuanalisis.
KONSEP PENGORGANISASIAN DIRIPETANI, LEMBAGA DAN ORGANISASI
Konsep Pengorganisasian DiriPengorganisasian diri merupakan
upaya individu (petani) untuk menjalankanusaha dan hidupnya dengan membangun danmenjaga relasi sosial (social relation) secararelatif tetap dan berpola dengan berbagaipihak di seputar dirinya. Seorang petani akan

131
PENGORGANISASIAN SECARA PERSONAL DAN GEJALA INDIVIDUALISASI ORGANISASI SEBAGAI KARAKTER UTAMAPENGORGANISASIAN DIRI PETANI DI INDONESIA Syahyuti
menjalin relasi dengan para pedagangpenyedia benih dan pupuk, dengan buruh tani,dengan penyedia jasa alat dan mesinpertanian, dengan pedagang pengumpul hasilpertanian, dan lain-lain termasuk denganaparat pemerintah. Lawrence et al. (2009)membahas konsep “pengorganisasian diri” inisebagai: “ … the ways in wich individuals,groups, and organizations work to create,maintain, and disrupt the institutions thatstructure their lives”.
Petani mengorganisasikan dirinyamelalui beberapa pilihan. Ia dapat masukkedalam organisasi atau dapat pula tidak. Jikatidak dalam organisasi, berarti petanimengorganisasikan dirinya di luar organisasidalam format individual action. Artinya, iamenggunakan relasi-relasi yang berbasispasar, bukan relasi berbasis organisasi(collective action). Petani memiliki kuasa danmampu memutuskan dengan siapa melakukantransaski dan menjalin interaksi untukmenjalankan usaha pertaniannya.
Jadi, pengorganisasian diri petanipada hakekatnya adalah suatu jejaring yangberisi sejumlah ”relasi sosial” yang salingterhubung di sekitar diri seorang petani.Jejaring seorang petani mungkin samapolanya dengan petani lain, namun orang-orang yang berada dalam jejaringnya dapatsebagian sama dan sebagian berbeda, atauberbeda sama sekali. Dalam setiap relasisosial terkandung materi, dimana setiap relasimerupakan satu yang berpola, dijaga, diulang,dan dimantapkan oleh petani dalamkesehariannya.
Pola ini sama-sama berlakusebenarnya baik dalam organisasi maupun diluar organisasi, yakni pada sistem pasar. Padaseorang petani yang masuk ke dalamorganisasi formal sekalipun, tidak akan hanyaberhubungan dengan sesama anggota danpengurus dalam organisasi tersebut, tetapijuga tetap menjalin relasi dengan orang-oranglain. Tidak ada petani di Indonesia yangseluruh hidupnya dijalankan dan digantungkanhanya pada organisasi formal. Yang terjadijusteru sebaliknya, meskipun seorang petanitelah masuk dalam organisasi formal, namunhampir seluruh aktivitas agribisnisnyadijalankan dari relasi dengan orang-orang di
luar organisasi. Artinya, petani tetapmengandalkan pada individual action, bukanpada collective action.
Meskipun secara administratif sudahjutaan petani masuk ke dalam organisasi,namun sesungguhnya tidak aktif (Bourgeois etal., 2003). Hampir semua urusan pertanianmulai dari memperoleh sarana usaha sampaidengan pemasaran, lebih sebagai tindakan-tindakan individual. Meskipun menjadianggota, mereka tidak mengandalkanorganisasi, karena tahu tidak banyak yang bisadiharapkan dari kemampuan organisasiselama ini.
Konsep Organisasi dan KeorganisasianKonsep “pengorganisasian diri” sangat
berbeda dengan konsep “organisasi”.Organisasi (organization) adalah kelompoksosial yang sengaja dibentuk oleh sekelompokorang, memiliki anggota yang jelas, dibentukuntuk mencapai tujuan tertentu, dan memilikiaturan yang dinyatakan tegas (biasanyatertulis). Organisasi adalah aktor sosial dalammasyarakat sebagaimana halnya individu.Contoh organisasi petani adalah koperasi,kelompok tani, gabungan kelompok tani, dankelompok wanita tani. Organisasi merupakansalah satu bentuk cara petani mengorganisasi-kan dirinya. ”Organisasi” merupakan elemendari lembaga (Scott, 1995; 2008), sebagai-mana juga paham dalam Teori EkonomiKelembagaan Baru. Organisasi adalah suatusocial group yang merupakan aktor sosial,yang sengaja dibentuk untuk tujuan tertentu,memiliki anggota secara jelas, dimana aturandinyatakan dan ditegakkan secara lebih tegas.
Sementara, keorganisasian (organiza-tional) adalah hal-hal berkenaan denganorganisasi. Disini tercakup misalnya perihalkepemimpinan dalam organisasi, keang-gotaan, manajemen, keuangan organisasi,kapasitas organisasi, serta relasi denganorganisasi lain.
Konsep Lembaga dan KelembagaanKhusus untuk lembaga (institution),
tidak sebagaimana dipahami selama ini,lembaga merupakan hal-hal yang menjadi

132
FORUM PENELITIAN AGRO EKONOMI, Volume 30 No. 2, Desember 2012 : 129 -145
penentu dalam perilaku manusia dalammasyarakat yakni berupa norma, nilai-nilai,aturan formal dan nonformal, dan penge-tahuan kultural (Scott, 2008). Keseluruhan inimenjadi pedoman dalam berperilaku aktor(individu dan organisasi), memberi peluang(empower) namun sekaligus membatasi(constraint) aktor. Seorang petani dapat sajamenjalankan hidupnya (=mengorganisasikandirinya) hanya dengan berpedoman padalembaga. Tanpa perlu organisasi (formal)petani bisa menjalannkan usaha dan hidup-nya. Sementara, kelembagaan (institutional)adalah segala hal yang berkenaan denganlembaga.
Sebagaimana dijabarkan secarapanjang lebar dalam Syahyuti (2010), kata”lembaga” adalah terjemahan langsung dari”institution”, dan ”kelembagaan” adalahterjemahan dari ”institutional”. “Lembaga”dapat dirumuskan sebagai hal yang berisinorma, regulasi, dan kultural-kognitif yangmenyediakan pedoman, sumber daya, dansekaligus hambatan untuk bertindak bagi aktor(Scott, 2008: 48). Fungsi lembaga adalahmenyediakan stabilitas dan keteraturan (order)dalam masyarakat, meskipun ia pun dapatberubah.
Demikian pula untuk petani, lembagamemberikan pedoman bagi petani dalammenjalankan aktifitasnya sehari-hari khusus-nya dalam bidang agribisnis. Berbagai normayang hidup di masyakat termasuk norma-norma pasar berserta seperangkat regulasimenjadi pertimbangan petani untuk bertindaksebagaimana ia memahaminya (kultural-kognitif). Lembaga tak hanya berisi batasan-batasan, namun juga menyediakan berbagaikriteria sehingga individu dapat memanfaatkanapa yang ia sukai (DiMaggio and Powell,1991). Lembaga memiliki dimensi preskriptif,evaluatif, and obligatory dari kehidupan sosial(Blom-Hansen, 1997) dan memberi kerangkasehingga identitas individu terbentuk (Marchand Olsen, 1984, 1989; Scott 1995). Ini sejalandengan Nee (2005) yang berpendapat bahwaaktor yang merupakan “aktor ekonomi” bukanseperti atom-atom yang lepas dari konteksmasyarakat tempatnya hidup, namun tidakpula sepenuhnya patuh pada aturan sosialyang hidup.
PENGORGANISASIAN SECARAPERSONAL SEBAGAI KARAKTER
PENGORGANISASIAN DIRI PETANIINDONESIA MASA LALU
Sebelum dikenal organisasi formal,petani telah mengorganisasikan dirinya (selforganizing) sedemikian rupa, denganmenyesuaikan pada kondisi dan hambatanalam, infrastruktur maupun sosial politik yangada. Mereka mengorganisasikan diri agardapat memenuhi semua kebutuhan hidupekonominya. Mereka membangun danmenjalankan berbagai relasi sosial atasberbagai basis relasi. Ada empat basis relasiyang terbangun, dimana antara keempatnyasatu sama lain saling tumpang tindih. Salahsatu bentuk yang selama ini dari berbagaipenelitian disebut sebagai “organisasitradisional” adalah apa yang disebut dalamtulisan ini hanya sebagai “pengorganisasiansecara personal”. Hal ini bukan organisasisebagaimana kita kenal dalam literatur teoriorganisasi. Sebutan sebagai “organisasitradisional” lahir karena menggunakan konsepdan teori organisasi sebagaimana dalam buku-buku teks selama ini.
Basis Relasi Patron-KlienHubungan patron klien adalah
pertukaran hubungan antara dua peran, yangmelibatkan seorang individu dengan statussosio-ekonominya yang lebih tinggi (patron)menggunakan pengaruh dan sumber dayanyauntuk menyediakan perlindungan, sertakeuntungan-keuntungan bagi seseorangdengan status yang dianggapnya lebih rendah(klien). Klien kemudian membalasnya denganmenawarkan dukungan umum dan bantuantermasuk jasa pribadi kepada patronnya(Scott, 1993). Hubungan patron-klien inimisalnya ditemukan pada masyarakat Bugis diSulawesi Selatan (Putra, 1988), yakni antara“Karaeng” sebagai patron dan “Ana-Ana”sebagai klien; juga di Jawa Barat yakni padamasyarakat suku Sunda (penelitian Adiwilagadalam Tjondronegoro dan Wiradi, 1984).Semenjak era Revolusi Hijau tahun 1980-an,pranata distributif dan hubungan patron klienini telah melemah (Wahono, 1994), yangdiindikasikan oleh penerapan upah uang tunaidan sistem “tebasan” dalam kegiatan panen.

133
PENGORGANISASIAN SECARA PERSONAL DAN GEJALA INDIVIDUALISASI ORGANISASI SEBAGAI KARAKTER UTAMAPENGORGANISASIAN DIRI PETANI DI INDONESIA Syahyuti
Relasi Berbasiskan Sentimen KekerabatanDisamping patron-lien, eksis pula
relasi yang berbasiskan etika jaminansubsistensi berupa sentimen primordial. Hidupberkelompok satu kerabat berdasarkan ikatangenealogis merupakan kelaziman, dimanakeluarga inti (nuclear family) dan keluarga luas(extended family) merupakan dua levelkelompok sosial yang memiliki fungsi langsungdalam urusan mata pencaharian anggotanya.Dalam kedua kelompok ini, terutama dalamkeluarga inti, setiap individu dapat menikmatibantuan utama dari sesamanya untuk dalamrangka pemenuhan kebutuhan dan keamananhidupnya (Koentjaraningrat, 1974).
Dalam suatu kelompok kekerabatan,mereka terikat oleh suatu sistem hak dankewajiban bagi para individunya terhadapsejumlah harta produktif , harta konsumtif, atauharta pusaka tertentu. Penelitian Syahyuti(2002) pada masyarakat pinggiran hutan diSulawesi Tengah menemukan bahwasentimen sesuku dan sub suku (suku Bugisdan Kaili) merupakan sumber daya yangpenting bagi petani untuk mendapatkan lahangarapan. Hal ini diperkuat Shanin (1990) yangmenyatakan bahwa pada eksistensi ”ekonomipeasant”, solidaritas keluarga menyediakankerangka dasar untuk saling membantu, salingmengontrol dan sosialisasi.
Basis Sentimen TeritoralSebagaimana ditemukan dalam
penelitian Scott (1993) pada masyarakatprakapitalis di Asia Tenggara, komunitas hidupsedesa menjamin kehidupan minimumwarganya melalui berbagai pengaturan yangmengedepankan prinsip mendahulukanselamat (safety first), meskipun tanggungjawab tersebut secara individual ada padapatron-patron yang ditekan oleh lembaga desasebagai pengawasnya. Kondisi seperti ini jugaterdapat di Jawa ketika masih berbentuk “desakomunal” (Temple, 1976), yang menciptakanjaminan kehidupan minimum bagi seluruhwarganya dengan jaminan semua anggotadesa bisa mengambil bagian dalam prosesproduksi. Tjondronegoro (1974) menemukankondisi ini pada level yang lebih kecil yaknipada kesatuan hidup sedusun (yang disebutdengan ”sodality”).
Ciri komunalitas hidup sedesa sangatterasa, yang secara tidak langsung dibentukoleh corak penguasaan tanahnya yang jugakomunal. Dalam pola ini, petani penggarapmenerima tanah desa atas kesepakatanbersama para anggota masyarakat sedesa(Brewer, 1985).
Pengorganisasian Secara PersonalPada banyak wilayah di pedesaan,
ditemukan tipe pengorganisasian, dimana alih-alih membentuk satu organisasi yangterstruktur dan dikelola beberapa orangpengurus, masyarakat desa cenderungmenunjuk satu orang untuk menangani satuurusan yang berkaitan dengan kebutuhansekelompok warga. Sekelompok orangmemberikan penugasan kepada satu orangdan melengkapinya dengan otoritas yangpenuh. Bukan sebagaimana organisasi formaldalam literatur, dimana ada sekelompok orangdengan kekuasaan yang terbagi danterstruktur secara berjenjang; pelaksanaantugas hanya dijalankan oleh seorang belaka(“pengorganisasian secara personal”).
Hal ini menonjol dalam pengelolaan airirigasi. Pimpinan subak di Bali, yang disebutdengan “pekaseh”atau “Klian Subak”mengoordinasi pengelolaan air berdasarkanaturan yang ada (awig-awig) (Teken, 1988).Meskipun dalam berbagai literatur, seorangKlian Subak disebut dengan pimpinan atauKetua Subak, namun posisi dankewenangannya tidaklah sebagaimana ketuadalam organisasi formal yang kita kenal.“Organisasi” yang menata keseluruhan fungsisubak itu sendiri melekat hanya pada diriseorang Klian Subak. Semua petani lebihmengenal dirinya, bukan pada “organisasi”nya, meskipun ia juga dibantu oleh beberapaorang tenaga lain.
Pola seperti ini juga ditemukan padasosok seorang “Ulu-Ulu” di wilayah JawaBarat, dan seorang “Kapalo Banda” di wilayahSumatera Barat. Dengan legalisasi dariseluruh petani di komplek persawahantertentu, dan berkuasa penuh dalam mengaturair, membaginya, menjaga saluran, danbahkan menghukum petani yang melanggar.Namun, Ulu-Ulu dan Kapalo Banda bukanlahsebuah organisasi, melainkan hanyalahseorang petugas yang diberi tugas dan

134
FORUM PENELITIAN AGRO EKONOMI, Volume 30 No. 2, Desember 2012 : 129 -145
kewenangan mengelola pengairan pada satuwilayah persawahan. Meskipun ia memilikipembantu, namun tanggung jawabnya penuhdan langsung kepadanya belaka.
Saat ini, meskipun desa-desa diIndonesia telah lama berada dalam intervensimodernisasi, namun bentuk-bentuk basisrelasi serta pola pengorganisasian seperti diatas masih eksis walaupun terbatas. Padawaktu bersamaan, saat ini telah eksis pulaorganisasi-organisasi formal petani, namunstruktur dan kultur di dalamnya tidaklahsebagaimana pola ideal secara teoritis.
GEJALA INDIVIDUALISASIORGANISASI PADA ORGANISASI PETANI
DI INDONESIA SAAT INI
Gejala “individualisasi organisasi”pada organisasi petani merupakan gejala yangumum dijumpai. Meskipun dari permukaanseolah organisasi dijalankan sesuai denganprosedur yang tertulis, namun sesungguhnyahanya dijalankan oleh segelintir pengurus,bahkan cenderung hanya oleh satu orang,biasanya adalah ketua organisasibersangkutan.
Dalam aktivitas sehari-hari, bahkansering sulit memisahkan antara kegiatanpribadi ketua dengan kegiatan organisasi.Artinya, berlangsung proses ”privatisasi” atau”individualisasi organisasi” pada diri pimpinanorganisasi. Organisasi menjadi identik denganketuanya belaka. Keberadaan dan eksistensipengurus organisasi jauh lebih nyatadibandingkan organisasi itu sendiri. Selainbahwa ketua yang akan bertanggung jawabjika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,keberhasilan sebuah organisasi jugadiidentikkan sebagai hasil kerja keras si ketuabelaka.
Dalam penelitian pada petani diwilayah Jawa Barat (Syahyuti, 2012), petugaspenyuluh lebih hafal nama ketua kelompok tanidibandingkan dengan nama kelompok taninya.Jika ada sesuatu yang harus disampaikan dandisikusikan, maka dengan mengkomunikasi-kannya dengan ketua, dianggap telah mewakiliorganisasi. Jika ada masalah berkenaandengan administrasi misalnya, petugas akanmemanggil dan mendiskusikan dengan ketua,bukan dengan sekretaris yang semestinya
bertanggung jawab. Ketua memahami posisiini, dan ia menjalankan organisasi dalamkerangka makna tersebut. Dalam persepsiketua, maju mundurnya organisasi tergantungpada dirinya. Demikian pula persepsi yangberkembang pada pengurus dan anggota,dimana keberhasilan sebuah kelompok tani,sebutlah terpilih sebagai kelompok taniteladan, semata-mata dipandang sebagaikeberhasilan ketua.
Gejala ini terbentuk setidaknya karenaempat alasan, yaitu: alasan pertama, karenajumlah dan tingkat tugas yang harus diembancukup mampu dijalankan oleh satu orangpengurus saja. Pada kelompok tani yangmasih pemula misalnya, seringkali tidakbanyak aktivitas yang harus dilaksanakan.Selain itu, banyak keputusan seringkali jugabisa ditetapkan sendiri oleh ketuanya tanpamendiskusikan dengan pengurus lain, mungkinkarena sudah sejalan dengan misi dan aturankelompok tani, sehingga tidak perlu lagididiskusikan. Kewenangan yang ada padanyacukup untuk mengambil keputusan langsungdan mandiri.
Aktivitas organisasi petani cenderungsederhana dan sangat terbatas. Jikadikomparasikan dengan teori, organisasiterlihat lemah dalam banyak sisinya misalnyadalam hal penyusunan perencanaanorganisasi, pertemuan rutin, pencatatanadministrasi, keuangan organisasi, dankegiatan monitoring dan evaluasi internal.Kinerja organisasi sangat terbatas, danaktivitas keorganisasian cukup mengandalkankepada ketua dan beberapa orang pengurus.Jika diukur menurut teori-teori organisasi,organisasi-organisasi milik petani dapatdisebut sangat lemah, bahkan bisadigolongkan sebagai “disorganized” atau 'notorganized'. Pergantian pengurus juga sangatjarang dilakukan, karena ada gejala dimanaumumnya petani menolak menjadi pengurus,bahkan cenderung takut (Syahyuti, 2010).
Jika dikembalikan kepada indikatorkemampuan kelompok tani yang saat iniditerapkan di jajaran Kementerian Pertanian,maka kondisinya relatif lemah untuk kelimaindikator, yakni kemampuan merencanakan,melaksanakan, pemupukan modal, meningkat-kan relasi dengan organisasi lain, sertakemampuan menerapkan teknologi. Selainsecara internal, kondisi organisasi milik petani

135
PENGORGANISASIAN SECARA PERSONAL DAN GEJALA INDIVIDUALISASI ORGANISASI SEBAGAI KARAKTER UTAMAPENGORGANISASIAN DIRI PETANI DI INDONESIA Syahyuti
lemah, jaringan antar organisasi juga terbatas.Ini juga ditemukan Lema dan Kapange ( 2006)di Tanzania, dimana tidak ada koordinasi antarorganisasi petani (farmer organization): “…..FO tends to operate informally and do notcomply with official legal requirements” (p. 77).
Alasan kedua, pengurus dan anggotamemberikan kepercayaan penuh kepada ketuauntuk memutuskan sendiri dengankewenangan penuh bagaimana berjalannyaorganisasi sehari-hari. Nilai dan norma dimasyarakat desa yang cenderung memilikitingkat kepercayaan (trust) tinggi menjadimodal bagi ketua untuk menggerakkanorganisasi. Sebaliknya, dari pihak penguruslain dan anggota, mereka percaya bahwaketua adalah orang yang dapat dipercaya danmampu menjalankan organisasi ke arah yangbenar. Alasan ini pulalah yang dalam kasustertentu menyebabkan terjadinya penyele-wengan keuangan misalnya, karena penga-wasan (self critics) dari pengurus dan anggotacenderung lemah.
Alasan ketiga, organisasi menerapkanprosedur non formal. Hal ini ditemukanBourgeois (2003) di Indonesia, yang jugadidukung temuan Lema dan Kapange ( 2006)di Tanzania, dimana farmer organization (FO)berjalan secara non formal. “FO tends tooperate informally and do not comply withofficial legal requirements” (p. 77). Secarasepintas, mereka menjalankan organisasiformal, namun jika digali lebih dalamsesungguhnya banyak prosedur danmanajemen yang berbeda dengan panduanformal semestinya.
Manajemen non formal disini dimaknaisebagai terciptanya prosedur dan struktur laindalam organisasi formal namun tidakmengikuti aturan yang ada atau tidaksebagaimana semestinya (merupakan suatumismanajemen). Hal ini terbentuk secaraspontan (evolving constantly), berakar daribawah (grass roots), dinamis dan responsif,memposisikan manusia sebagai individual,bersifat datar dan mengalir (flat and fluid), danbertahan karena adanya kepercayaan danresiprositas (trust and reciprocity). Respon inisesuai untuk situasi yang berubah cepat danseringkali tidak mudah dipahami.
Alasan keempat, organisasi menerap-kan kultur pragmatis. Pendekatan yang kurangmemberi kematangan proses organisasi
menyebabkan tidak berkembang kulturorganisasi secara mandiri. Dalam dokumen-dokumen organisasi, baik struktur, nilai, visi,norma, maupun manajemen organisasimenggunakan pedoman yang sudah baku danbersifat umum seluruh Indonesia. Setiaporganisasi petani harus mengadopsi pedomanini.
Namun dalam perkembangannya,organisasi tidak menjalankan organisasisesuai dengan prosedur tersebut. Organisasipetani cenderung mengembangkan kulturyang pragmatis (pragmatic culture). Kuatnyatekanan luar, sementara permasalahaninternal organisasi berkembang ke arah yangberagam, maka pengurus organisasimenjalankan kultur yang cenderung kooperatif.Organisasi lebih mengutamakan kepuasanpihak-pihak lain (their clients) terutamapemerintah, meskipun sesungguhnya tidakmengikuti kesepatakan dan prosedur yangtelah dituliskan dalam dokumen.
Peran aktor dalam organisasi danfungsi bagian-bagian organisasi telahbergeser. Respon seperti ini karena terlalukuatnya tekanan lingkungan, juga ditemukanWijayaratna (2002) di Nepal, dimanaorganisasi-organisasi petani mengambil sikappragmatis (“form follow function”). Organisasimelakukan adaptasi ketika terjadi perubahankondisi lingkungan sosial dan kulturalnya. Cirikarakteristik organisasi dengan kulturpragmatis ini adalah dimana hasil lebihdiutamakan dibandingkan prosedur, danorganisasi dipandang sebagai struktur networkyang mengalir (fluiding network structure).Organisasi melakukan adaptasi terhadaptekanan dan kebutuhan dengan perubahan-perubahan lingkungan yang berlangsung.
Karakter non formal dan kulturpragmatis terjadi karena begitu kuatnyatekanan lingkungan kepada organisasi,terutama dari pihak pemerintah. Hal inimenyebabkan sempitnya ranah organisasi(organization field). Individualisasi organisasimerupakan respon terhadap kuatnya tekanantersebut, yang oleh pengurus organisasi laludipadukan secara cerdik dengan kebutuhaninternal, atau setidaknya pemaknaannya (selfmeaning) terhadap permasalahan dankebutuhan internal organisasi.
Salah satu dampak dari individualisasiorganisasi ini adalah organisasi biasanya

136
FORUM PENELITIAN AGRO EKONOMI, Volume 30 No. 2, Desember 2012 : 129 -145
langsung menurun kinerjanya jika terjadipergantian ketua. Bagi anggota lain merupa-kan sebuah tindakan yang kurang beretika jikamenggantikan kedudukan seorang ketua yangdianggap telah banyak berjasa. Rasa sungkandan enggan menyebabkan sulitnyaberlangsung reposisi dan regenerasi dalamorganisasi. Merupakan hal yang umum,dimana seorang ketua yang dianggap suksesmemimpin organisasi sampai belasan bahkanpuluhan tahun (Saptana et al., 2003)
PROSES EVOLUSI PENGORGANISASIANDIRI PETANI
Kedua bentuk ini, yaitu pengorganisa-sian secara personal dan individualismeorganisasi, sesungguhnya berlangsung
sebagai sebuah evolusi yang terjadi secarakronologis. Pengorganisasian secara personalberlangsung dahulu ketika belum diintroduksi-kan organisasi-organisasi formal olehpemerintah. Organisasi formal diperkenalkandan menjadi satu-satunya bentuk pengorgani-sasian diri petani semenjak era Bimas sampaiInsus dan Supra Insus, sehingga saat terakhirini.
Selanjutnya individualisasi organisasimerupakan sebuah gejala yang berlangsungsetelah berbagai organisasi diperkenalkan dandiintroduksikan. Ini merupakan reaksi kritis daripetani menghadapi keharusan untuk hidupdalam organisasi. Format dan strukturorganisasi formal dengan segala etika danprosedurnya tampaknya dinilai terlaluberlebihan oleh petani, padahal urusan yangharus dijalankan tidak membutuhkan
Tabel 1. Matrik Perbedaan Bentuk dan Karakter antara Pengorganisasian Secara Personal, Organisasi Formal,dan Gejala Individualisasi Organisasi
Aspek Pengorganisasian secarapersonal Organisasi formal Gejala individualisasi
organisasiMasa terbentuknya Dahulu, sebelum
diintroduksikan organisasiformal oleh pemerintah
Masa revolusi hijau, mulaidari era Bimas, Insus,Supra Insus, dan sampaisekarang
Setelah diintroduksikanorganisasi formal.
Alasan terbentuknya Secara alamiah, denganalasan efisiensi manajemen
Sesuai dengan teoriorganisasi yang diadopsioleh pemerintah
Merupakan respon kritisterhadap format organisasiformal yang dipandangkurang sesuai dan tidakefisien
Ciri kepemimpinan Mutlak, hanya di tangansatu orang (mis. “KapaloBanda” dan “Ulu-Ulu”)
Bersifat kolegial Secara faktual bertumpupada seorang pengurusorganisasi saja
Distribusi kekuasaan Sentralisasi pada satuorang penanggung jawab
Terdistribusi antara ketua,sekretaris, bendahara,seksi-seksi, dan lain-lainpengurus organisasi
Secara faktualtersentralisasi, karena hanyadijalankan satu orangpengurus, biasanya ketuaorganisasi
Peran dan sosokpemimpin
Lebih sebagai penerimabeban dan penanggungjawab operasional
Demokratis danprosedural sesuai AD danART
Kurang demokratis dan tidakprosedural. Semua urusanditangani sendiri, termasukperan pengurus organisasiyang lain
Posisi anggota Petani adalah pihak yangmemberikan “tugas” danmenyerahkan kuasa penuhkepada pengurus
Kuat secara administratif,sesuai dengan AD danART organisasi
Lemah dan pasif. Anggotamerasa berhutang budikepada jasa ketuaorganisasi
Masa kepengurusan Lama, sering tidak terbatas Terbatas, biasanya 3-4tahun, sesuai dengan AD,ART dan rapat angota
Faktanya masakepengurusan lebih lamadari ketentuan, dan seringtidak diganti sampai belasantahun

137
PENGORGANISASIAN SECARA PERSONAL DAN GEJALA INDIVIDUALISASI ORGANISASI SEBAGAI KARAKTER UTAMAPENGORGANISASIAN DIRI PETANI DI INDONESIA Syahyuti
manajemen yang kompleks tersebut (Saptanaet al., 2003).
Jadi, urutan proses terbentuknyabentuk-bentuk pengorganisasian diri ini adalahdimulai oleh bentuk pengorganisasian secarapersonal, lalu diintroduksikan bentukorganisasi formal, namun akhirnya yangbanyak berlangsung secara riel adalah gejalaindividualisasi organisasi. Matrik berikutmemaparkan perbedaan ketiga karakterpengorganisasian diri tersebut.
Dari sisi alasan terbentuknya polademikian, terdapat alasan yang sama yaknikemudahan atau efisiensi. Dengan bebantugas yang dipersepsikan tidak rumit, makadengan memberikan tugas mengaturpengairan hanya kepada seorang sajadipandang sebagai sebuah cara yang rasional.Demikian pula dengan gejala mengapaakhirnya cukup seorang ketua kelompok tanisaja yang menjalankan kelompok tani.Disrtibusi kekuasaan pada hakekatnya adalahmemusat (centralized), namun hal itudipandang lebih menjamin tersedianyapelayanan bagi anggota.
Khusus untuk kepemimpinan, gambarberikut ini memvisualisasikan kondisi yangterjadi. Pada bentuk pengorganisasian secarapersonal, kekuasaan terbesar hanya padaseorang saja, yakni “Kapalo Banda” atau “Ulu-
Ulu”. Jika pun ada orang lain yang membantu,posisinya adalah pembantu yang tidak diserahibeban khusus. Seorang penjaga pintu airmisalnya tidak dapat dimintakan tanggungjawab oleh petani, karena ia bertanggungjawab ke atas yakni kepada “Ulu-Ulu” secarapenuh.
Gejala individualisasi organisasi tidakterlihat di permukaan, dan cenderungdisembunyikan. Hal ini merupakan suatu yangtidak prosedural dan merupakan keputusannon formal yang hanya menjadi kesepakatandiam-diam, dan tidak terbaca pada berbagaiperaturan dan kesepakatan dalam organisasi.Ini merupakan reaksi dari tekanan formal yangdihadapinya.
Petani menghadapi tekanan formalitas(formalitas pressure) dalam hidup sehari-hari.Intervensi organisasi (organisationalinterventions) memberi kerangka kepadaperilaku petani . “…. like institutions,organisations provide a structure to humaninteraction - but they are the players of thegame rather than the rules” (North, 2005).
Bagi petani, lingkungan formal tidakselalu merupakan kondisi yang kondusif.Dalam posisi dimana sebagian besar petanitidak berorganisasi secara formal, atau hanyaorganisasi yang belum kuat; maka lingkunganformal lebih terasa sebagai mengucilkan
Gambar 1. Perbedaan Posisi dan Kuasa Pemimpin pada Bentuk Pengorganisasian Secara Personal,Organisasi Formal, dan Gejala Individualisasi Organisasi

138
FORUM PENELITIAN AGRO EKONOMI, Volume 30 No. 2, Desember 2012 : 129 -145
mereka. Penelitian White (1997) di duawilayah di dataran tinggi di Jawa Baratmenemukan bahwa pola relasi berupa kontrakyang dijalankan dalam organisasi tidak selalumenguntungkan untuk mereka, baik padapetani kelapa maupun peternak sapi perah.
Organisasi formal sebagai strategiyang cenderung menjadi “keharusan” terbacapada berbagai peraturan, pedoman, danpetunjuk teknis yang dikeluarkan pemerintah,terutama pada instansi KementerianPertanian. Pada Pedoman UmumPengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan(PUAP) Tahun 2011 misalnya, pada bagiantujuan disebutkan bahwa PUAP bertujuanuntuk “meningkatkan fungsi kelembagaanekonomi petani menjadi jejaring atau mitralembaga keuangan dalam rangka akses kepermodalan” (point d). Lalu, pada bagiansasaran disebutkan, sasaran PUAP adalahjuga berkembangnya 10.000 Gapoktan yangdimiliki dan dikelola oleh petani untuk menjadikelembagaan ekonomi (point b).
Berikutnya, pada dokumen PedomanPelaksanaan Penerimaan dana bantuan SosialTA 2011 Direktorat Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.Pada bab II (Mekanisme PenetapanKelompok), bagian sasaran, disebutkan bahwa“kelompok sasaran ialah kelompok yang telahada dan menjalankan usaha agribisnis danatau ketahanan pangan ….”.. Pada bagianselanjutnya ditambahkan persyaratan:“Peternak atau warga masyarakat sasaransebagai penerima Dana Bantuan Sosial, yaituanggota kelompok sasaran yang ditetapkandengan keputusan Bupati/Walikota”.
Contoh berikutnya, Permendagri No32 Tahun 2011 tentang Pedoman PemberianHibah dan Bantuan Sosial yang Bersumberdari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah. Pada Pasal 7 ayat 1 dan 2menyatakan bahwa hibah kepada masyarakatdiberikan dengan persyaratan paling sedikit“...memiliki kepengurusan yang jelas”, dantelah terdaftar pada pemerintah daerahsetempat sekurang-kurangnya 3 tahun.
Organisasi formal dipilih pemerintah,karena negara adalah sebuah organisasiformal yang basis manajemennya adalahformalitas dalam segala sisi aktivitasnya.Untuk menjalankan pembangunan pertanian,pemerintah merasa tidak cukup jika hanya
memberi benih, pupuk, dan lain-lain; namunjuga mengendalikan petani. Artinya,pemerintah berupaya mengorganisasikan diripetani. Pemerintah ingin mengendalikanpetani, apa yang harus ditanam petani,bagaimana menanamnya, dan dengan siapapetani semestinya berhubungan. Menggiringpetani masuk kedalam organsiasi formal (misalkelompok tani) merupakan bentuk untukpengendalian tersebut. Organisasi formalmerupakan alat untuk berhubungan denganpetani. Relasi antar organisasi yang berjalandalam suasana formal diyakini akan lebihefektif, karena lebih terkontrol dan dapatdiduga (predictable).
Kondisi yang berlangsung merupakanhasil dari format politik pertanian Indonesiayang mensubordinasi petani yang sejakdahulu. Pada era kerajaan, petani padahakekatnya adalah “milik raja” yang bekerja ditanah raja. Demikian pula di era kolonial,dimana bahkan petani harus menjadipenyewa, karena semua tanah adalah milikpemerintah (Fauzi, 2002). Lalu, pada era OrdeBaru dalam format modernisasi, petanimenjadi penyedia tenaga kerja murah untukindustri (Martinussen, 1997). Sesuai denganMartinussen (1997), organisasi telah dijadikansebagai alat atau wadah untuk berpartisipasi,namun dalam konteks untuk memudahkankontrol oleh negara. “… participation wascarefully organized and controlled (p. 232).
Fenomena ini sejalan dengan TeoriUrban Bias dari Lipton (1977), yakni adanyakonflik antara rural classes dengan urbanclasses, dan gejala “bureaucratic polity”(Jackson and Pye, 1978). Semenjak OrdeBaru, petani menghadapi kekuatan yang sulitdihadangnya. Hal ini dituliskan secara jelasoleh Bourgeois (2003: 6), yaitu: “ Theiraspirations, what they would really like toachieve and how they would like to developtheir activities, are constrained by the fact thatthey face stakeholders (government, traders)whose logics are different and prevail in thecurrent socio-political and economic system”.Intervensi pemerintah yang top-down telahmenumbuhkan sikap pasif pada petani,sehingga organisasi petani (rural producer’sorganization) yang terbangun bukanmerupakan ekspresi diri petani itu sendiri.
Tanpa sadar berlangsung prosespenghancuran komunitas karena introduksi

139
PENGORGANISASIAN SECARA PERSONAL DAN GEJALA INDIVIDUALISASI ORGANISASI SEBAGAI KARAKTER UTAMAPENGORGANISASIAN DIRI PETANI DI INDONESIA Syahyuti
relasi-relasi formal ini (Saptana et al., 2003).Pada beberapa lokasi, khusus untukorganisasi yang dapat disebut berhasil, antarapemerintah dan petani berhasil ditumbuhkansikap kepemilikan bersama (sense of sharedownership) (Wijayaratna, 2002). Dalam kondisiini, organisasi disadari oleh petani sebagai“milik bersama” antara dirinya denganpemerintah.
Sikap mengintroduksikan organisasiformal ke petani seperti ini telah banyakmenuai perdebatan. Dari penelitian pada limakesatuan wilayah irigasi (di Thailand,Myanmar, Vietnam dan Sri Langka), Pereramenemukan bahwa petani tidak berorgansiasisecara formal namun terbukti mampumengelola pengairan dengan efektif. “In manycases they are not organization at all” (Perera,2004).
RESPON RASIONAL-KREATIF PETANITERHADAP LINGKUNGAN KELEMBAGAAN
SEBAGAI DASAR TERBENTUKNYAPENGORGANISASIAN DIRI PETANI
Merupakan hal yang menarik menje-laskan mengapa petani menjalankan hidupnya(mengorganisasikan dirinya) dengan carademikian? Mengapa petani menjalankanprosedur yang non formal dan berlangsunggejala individualisasi organisasi? Dalam men-jalankan usaha pertaniannya, petani meng-hadapi kerangka kelembagaan (institutionalframework) yang memberi batasan sekaliguspedoman baik dalam posisinya sebagaiindividu maupun sebagai anggota dalam satuorganisasi. Lingkungan utama yang dihadapipetani tersebut adalah regulasi pemerintahyang berkenaan dengan berbagai sisipembangunan pertanian.
Pada sebagian besar literatur,mengapa petani memilih tidak berorganiasiselalu menyalahkan petani, yakni “karenakesadaran yang kurang”. Jawaban ini datangdari sikap empati yang lemah terhadap petani,dan cenderung sepihak yang kaku denganteori organisasi. Namun, disini penulis mencaripenjelasan penyebab ini pada diri petanisendiri sesuai dengan kondisi yangdihadapinya. Sesuai konsep kelembagaanbaru (Scott, 2008; Nee, 2005), petani adalahaktor sosial yang rasional-kreatif. Petani
diyakini mampu mengambil keputusan apayang terbaik untuk dirinya, yakni dengan siapaakan berinteraksi dan bagaimana polapengorganisasian dirinya sebagai keputusandirinya sendiri. Dalam menetapkan pilihannya,petani mempertimbangkan sekaligus dansecara bersamaan antara tekanan pemerintahdan pasar, serta terhadap komunitas.Menghadapi lingkungan kelembagaan yangmelingkupinya dan pemaknaan aktif aktorterhadap lingkungan, melahirkan berbagaibentuk respon.
Tekanan Formalitas dari Negara, NormaEkonomi Pasar, dan Norma Hidup dalamKomunitas
Masyarakat dipenuhi oleh berbagaiaturan, dan manusia berperilaku denganmelihat pada aturan-aturan tersebut. Manusiaakan berusaha memaksimalkan keuntunganuntuk dirinya, dengan menggunakan atauberkelit dari aturan-aturan yang ada tadi.Objek perhatian pada bagian ini adalah aturan(rule) yang ada, dan “keuntungan apa” yg akandiperoleh pelaku dalam bertindak (Portes,2006). Dalam perspektif ini, manusiadipandang sebagai makhluk yang rasional. Inisejalan dengan Nee (2005) yang berpendapatbahwa aktor yang merupakan “aktor ekonomi”bukan seperti atom-atom yang lepas darikonteks masyarakat tempatnya hidup, namuntidak pula sepenuhnya patuh pada aturansosial yang hidup.
Selain pemerintah dan pasar, petanijuga mempertimbangkan norma hidupberkomunitas. Parsons menyebutkan bahwa”sistem normalah yang mengatur relasi antarindividu, yakni bagaimana relasi individusemestinya” (Scott, 2008). Pada prinsipnya,norma (how things should be done) akanmenghasilkan preskripsi, bersifat evaluatif,dan melahirkan tanggung jawab dalamkehidupan aktor di masyarakat. Normamemberi pengetahuan apa tujuan kita, danbagaimana cara mencapainya. Norma bersifatmembatasi (constraint) sekaligus mendorong(empower) aktor. Kompleks norma padahakekatnya menjelaskan apa kewajiban bagiaktor (supposed to do).
Norma dapat menjadi sumberdayayang kuat dalam menjalankan usaha pertaniandan kehidupan. Norma merupakan jalan yang

140
FORUM PENELITIAN AGRO EKONOMI, Volume 30 No. 2, Desember 2012 : 129 -145
efisien untuk mencapai kesejahteraan,mengatasi kegagalan pasar, dan menekanbiaya sosial. Norma juga dapat mengatasipermasalahan tindakan kolektif. Norma-normaini cukup bagi petani untuk menjalankanusahanya tanpa membutuhkan organsisasiformal, yakni berupa norma-normakekerabatan dalam sentimen primordial,norma-norma hidup dalam komunitas, norma-norma berkenaan dengan relasi dengan orangluar terutama dengan pemerintah, sertanorma-norma berkenaan dengan relasi pasar.
Petani melakukan pemaknaan danrespon aktif terhadap aturan dan norma.Petani membangun sikap berbeda antararelasi dengan pasar dengan relasi denganpetugas pemerintah. Komunikasi pasarberlangsung melalui transaksi dengan hargasebagai message-nya, sementara negaramengandalkan kepada otoritas dan power.Pasar memiliki legitimasi perhitungankomersial (comercial imperative), bukanberupa imbauan moral (moral imperative).Implikasinya, petani memenuhi tuntutan pasardengan pragmatis, sedangkan untuk himbauanpemerintah (misalnya himbauan untukberorganisasi) dipenuhi sesuai dengan tingkatpemaksaan yang dirasakan. “Pemaksaan”berorganisasi melekat pada prosedur, dimanahanya melalui organisasi bantuan daripemerintah bisa diterima oleh petani.
Bagi petani, aktivitas bertani tetap bisaberjalan tanpa organisasi, karena lembagasesungguhnya telah memberi cukup pedomandan kesempatan. Dengan kegiatan yang harusdijalankan dan pilihan yang harus diambil,tanpa berorganisasipun petani merasa telahdapat menjalankan hidupnya. Intinya, bagipetani, organisasi bukan social form yangdipandang lebih efektif dalam kehidupansosial. Bagi petani organisasi bukan bentukyang efektif.
Sebagi aktor yang rasional-kreatifrealitas organisasi bagi petani adalah bahwaorganisasi sebagai wadah untuk berinteraksidengan pemerintah, sebagai suatu proseduryang harus dipenuhi untuk mengkasesbantuan dari pemerintah, sebagai jalan untukterlibat dalam pembangunan, dan agardianggap sebagai masyarakat yangpartisipatif. Secara internal, organisasi jugadimaknai sebagai jalan untuk mengkolektifkankegiatan secara horizontal. Berbagai norma
yang hidup di masyakat termasuk norma-norma pasar berserta seperangkat regulasi,menjadi pertimbangan petani untuk bertindak -atau tidak bertindak - sebagaimana iamemahaminya (kultural-kognitif).
Relasi Sosial Individual Sebagai IntiPengorganisasian Diri Petani
Sebagian besar petani saat inimenjalankan usaha agribisnis yangdikelolanya dengan menjalin relasi-relasi yangberbentuk “relasi individual” (individual socialrelation) dengan berbagai mitra kerjanya, baikdengan pemasok input usaha, butuh tani, danpedagang pengumpul. Petani membuatkeputusan untuk berelasi dengan sejumlahaktor lain secara pribadi, tanpa melibatkankelompoknya. Selanjutnya, petani jugamelakukan transaksi dan menjaga relasi yangdibangun tadi juga dalam konteks keputusanindividual.
Relasi-relasi individual tidakmengandalkan kepada organisasi atau oranglain. Dalam konteks ini, petani sebagai aktorsosial (social actor) tidak mewakilkan relasinyakepada pihak lain. Hal ini tidak sebagaimanagambaran tindakan kolektif, dimana aktormewakilkan tindakannya ke orang lain.Tindakan individual (individual action) mereferkepada tindakan yang diambil oleh seseorangyang didasarkan atas putusannya sendiri.
Ada banyak alasan pokok mengapapetani lebih memilih tindakan atau relasiindividual. Alasan yang sangat masuk akaladalah karena ketersediaan relasi dimanapelayanan untuk berusahatani sudah cukupmemadai. Saat ini petani dengan mudah dapatmembeli benih, pupuk dan berbagai kebutuhanlain dari kios-kios yang menjualnya di desamaupun di pasar terdekat. Petani dapatmembayar tunai ataupun berhutang (pola“yarnen”) terhadap barang yang dibelinya.Demikian pula untuk kebutuhan lain, misalnyamemperoleh air irigasi, mendapatkan buruhtani dan menjualkan hasil panennya.
Dengan demikian, petani yangmenggunakan relasi individual dapatdipandang sebagai hal yang rasional. Kedepan, jika pelayanan ekonomi untuk usahapertanian semakin mudah diakses petani,maka tipe relasi ini bisa semakin berkembang.

141
PENGORGANISASIAN SECARA PERSONAL DAN GEJALA INDIVIDUALISASI ORGANISASI SEBAGAI KARAKTER UTAMAPENGORGANISASIAN DIRI PETANI DI INDONESIA Syahyuti
Selain itu, alasan lain adalah karenakondisi organisasi yang belum mampumewadahi semua kebutuhan petani.Lemahnya organisasi ini salah satunya karenasemangat tindakan kolektif yang rendah.Sebagaimana dalam teori, musuh utamasulitnya mencapai tindakan kolektif adalahsikap penunggang bebas (free rider).Fenomena ini juga banyak ditemui dimanamaju mundurnya organisasi cenderungdiserahkan kepada pengurus saja.
Dalam kehidupan organisasi, bebe-rapa relasi merupakan relasi yang sifatnyahanya pendukung atau merupakan relasi yangtak langsung, misalnya berupa rapat-rapatuntuk menyusun perencanaan. Sementaradalam pasar relasi bersifat langsung. Semuarelasi sosial yang berlangsung di pasar adalahrelasi langsung belaka, dan tak ada yangpercuma. Sebagai contoh, petani menghu-bungi seorang pedagang untuk memberitakanbahwa ada gabah yang mau dijualnya, danlangsung menegosiasikan harga. Relasi inibersifat tuntas dan ringkas.
Bahkan adakalanya sebagian petanimenggunakan organisasi untuk mendukungtujuan-tujuan individualnya. Hal ini terjadi padapengurus organisasi, yang karena kewe-nangan yang dimilikinya dalam organisasi,mengembangkan kapasitas dan meningkatkanrelasinya dengan berbagai pihak. Posisisebagai ketua Gapoktan memberi keuntunganyang banyak karena posisinya yang sentral,dan dapat pula berkomunikasi secara intensifdengan banyak staf pemerintah. Sebagaimanadijelaskan di bagian lain, sumber daya daripemerintah merupakan sumber daya utamayang menggerakkan kegiatan pertanian didesa penelitian.
Lembaga cukup bagi petani untukmengorganisasikan dirinya. Lembagalah -bukan organisasi – yang menjadi pedomandan basis dalam membangun sejumlah relasisosial bagi petani untuk menjalankanusahanya. Meskipun ada belasan organisasidalam satu desa, tapi hampir semua relasiyang dijalankan petani, merupakan relasiindividual, bukan suatu tindakan kolektif yangdiwakilkan kepada organisasi.
Kondisi ini memungkinkan, sebagai-mana pengalaman Lobo (2008) dalam
kegiatan lapangan, karena lembaga mampudan menjadi penting karena dapatmenentukan dan membentuk bagaimanaproses pertukaran dan intekasi sosial, politik,kultural dan ekonomi berlangsung. Lembagajuga menetapkan batasan pilihan (range ofchoices), pengaturan risiko dan ketidakpastian,dan menentukan biaya transaksi dan produksi.Lebih jauh, ia juga mempengaruhi feasibilitasdan keuntungan dalam aktivitas ekonomi.Lembaga bahkan “…. evolve incrementally,linking the past with the present and future”.Lembaga mampu menghubungkan masa lalu,sekarang dan masa depan. Lembagamenentukan bagaimana insentif akan terbagidalam masyarakat: siapa mendapat apa danberapa banyak.
Organisasi bersama lembaga menjadisumberdaya dalam pengorganisasian diripetani. Petani menggunakan organisasi seba-gai salah satu sumber daya, sebagaimanasumber daya lainnya dalam lembaga. Berlang-sung proses yang saling mencampurkan(interplay) antara aspek regulatif, normatif dankultural kognitif dengan organisasi formal.
Lebih jauh, petani telah memberikanmakna yang sama sekali baru terhadaporganisasi, yang sungguh berbeda sebagai-mana diinginkan oleh pemerintah. Bagi petani,organisasi dijadikan modal dalam membentukdan menjaga relasi dengan aparat pemerintah.Petani tidak memberikan sikap resistensi -namun justeru kooperatif - dan malah tetapmampu menarik manfaat dari relasi tersebut.
Dengan demikian, yang lebihdibutuhkan adalah pengorganisasian petanidalam makna luas. Insentif untukberorganisasi secara formal lemah, karenaselain pembentukan organisasi membutuhkanketerlibatan yang cukup menyita waktu,pelayanan untuk menjalankan usaha telahcukup tersedia di desa. “Organisasi” yangdibutuhkan bercirikan sebuah bangunan sosialyang mampu memberikan akses petaniterhadap segala kebutuhannya. Organisasi inimampu membantu berbagai hambatan yangdihadapi petani dan mitranya misalnyapedagang kecil lokal, dalam hal pengetahuandan keterampilan, teknologi dan kualitasproduk, skala ekonomi, biaya transaksi yangmahal, dan rendahnya akses ke permodalan.

142
FORUM PENELITIAN AGRO EKONOMI, Volume 30 No. 2, Desember 2012 : 129 -145
PENUTUP
Berdasarkan analisis kelembagaan,dimana relasi sosial menjadi inti perhatiannya,petani menjalankan usahanya (mengorganisa-sikan dirinya) melalui pola-pola yang tidakkaku sebagaimana organisasi formal saja.Bagi petani, organisasi formal hanyalah satupilihan, dan bahkan lebih menjadikan tindakanindividual (individual action) sebagai bentukyang pokok.
Petani menjalankan usaha pertanian-nya melalui pedoman norma dan regulasi,dengan melakukan pemaknaan aktifterhadapnya. Petani menjalin relasi-relasisosial dengan berbagai pihak denganberpedoman kepada panduan normatifkomunitas, norma ekonomi dalam pasar, danrelasi dengan petugas pemerintah. Dalamkondisi ini, organisasi formal (kelompok tani,koperasi, Gapoktan, dan lain-lain) hanyalahsalah satu sumber daya bagi petani yangbersama-sama unsur-unsur dalam lembagadijadikan sebagai peluang, pedoman, sertabatasan untuk berperilaku sehari-hari.
Organisasi formal yang diintroduksikanpemerintah dimaknai dan direspon dalamkerangka lembaga tersebut. Salah saturesponnya adalah dimana organisasi petanihanya dijalankan oleh sejumlah kecilpengurus, dan eksistensi organisasi hanyamengandalkan pada mereka, sehinggaberlangsung gejala “individualisasi organisasi”.Pola manajemen organisasi seperti ini menirubentuk pengorganisasian masa lalu yangmemberikan kewenangan dan peran padaseseorang saja (=“pengorganisasian secarapersonal”). Fenomena ini biasa ditemukanpada pengelolaan irigasi skala kecil yangdisebut dengan Ulu-Ulu di Jawa Barat, KapaloBanda di Sumatera Barat, dan Klian Subak diBali, yang merupakan sebuah “individualautonomous”. Seseorang yang ditunjuk diberiwewenang penuh untuk mengelola irigasi, danberhak menetapkan bagaimana pembagianair, menyusun rencana, termasuk membuatkeputusan untuk mengundang petani dalamberbagai kepentingan.
Dengan segala permasalahan danpilihan yang mereka hadapi, relasi individualyang berbasiskan komunitas dan pasarterbukti lebih banyak dipilih petani. Temuan ini
sedikit banyak dapat menjadi catatan, bahwaselain relasi individual ini perlu diperhatikan,petani dengan ciri seperti ini membutuhkanbangun organisasi yang berbeda. Relasi-relasiberbasis pasar pada hakekatnya adalahsebuah organisasi dalam arti luas. Didalamnya juga dijumpai pelaku-pelaku yangdapat dibatasi secara sosial, relasi-relasi danstruktur relasi yang terpola, norma yangdipegang dan dijaga bersama (meskipun tidaktertulis), serta transaski yang murah danefektif. Namun, bentuk pengorganisasianberbasis pasar tidak selalu lebih baik.Bagaimana bentuk pengorganisasian yangsesuai bergantung pada kompleks norma,aturan, serta kultural kognitifnya yaitubagaimana petani memahami kondisi yangdihadapinya.
Sikap pemerintah selama ini yangmenjadikan organisasi formal sebagai satu-satunya jalan untuk menggerakan dalampemberdayaan, merupakan pendapat yangsudah waktunya direvisi. Selain anjuran inikurang disukai petani, pemaksaan iniberdampak timbulnya banyak masalah dilapangan, misalnya berlangsungnya kebo-hongan administratif, program yang tidakefektif mencapai petani yang semestinya, danmembuat manfaat pembangunan kurangterdistributif secara adil. Pemberian bantuankepada masyarakat yang menurut aturanhanya dapat diberikan kepada organisasiformal semestinya ditiadakan, karena tidakakan mampu mencapai petani-petani kecil danmiskin yang sesungguhnya jauh lebihmembutuhkan. Pengorganisasian petani tanpaharus berada dalam organisasi formal adalahimplikasi yang masuk akal sebagaimanatemuan dan analisis dalam penelitian ini.
Sesuai dengan pendekatan TeoriKelembagaan Baru, organisasi petani dalambentuk formal semata-mata mestilah hanyadipandang sebagai pilihan. Untuk berjalannyapembangunan pertanian, atau aktivitasagribisnis khususnya, yang dibutuhkan adalahpengorganisasian petani (dalam makna luas)yang efektif. Setiap transaksi dapat dijalankandengan biaya murah, dan tersedia jaringanantar pelaku dengan bentuk terpola sehinggadapat menjadi wadah yang dapat diaksespetani dengan mudah. Pengorganisasianpetani pada hakekatnya merupakan upayauntuk menjalankan tindakan kolektif, dengan

143
PENGORGANISASIAN SECARA PERSONAL DAN GEJALA INDIVIDUALISASI ORGANISASI SEBAGAI KARAKTER UTAMAPENGORGANISASIAN DIRI PETANI DI INDONESIA Syahyuti
keyakinan bahwa tindakan kolekif lebih murahdan efektif. Namun, dalam kondisi lingkungankelembagaan yang baik, tanpa tindakan kolekiftetap mampu dicapai kemudahan. Dengandemikian, perbaikan ke depan dapat melaluiaras lembaga (dan kelembagaan) maupunmelalui aras organisasi.
DAFTAR PUSTAKA
Beard, Victoria A. and A. Dasgupta. 2006.Collective Action and Community-drivenDevelopment in Rural and Urban SagePublication and Urban Studies JournalLimited. http://usj.sagepub.com/cgi/content/abstract/43/9/1451
Blom-Hansen, J. 1997. A ‘New Institutional’Perspective On Policy Networks, PublicAdministration 75: 669–693.
Bourgeois, R.F. Jesus; M. Roesch, N. Soeprapto, A.Renggana, dan A. Gouyon. 2003.Indonesia: Em-powering Rural ProducersOrgani-zation. Rural Development andNatural Resources East Asia and PacificRegion (EASRD).
Branson, J. and D. Miller. Pierre Bourdieu. Hal. 43-57. dalam: Peter Beilharz. 2002. Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis terhadapPara Filosof Terkemu-ka. Pustaka Pelajar,Yogyakarta.
Brewer, J.D. 1985. Penggunaan Tanah Tradisionaldan Kebijakan Pemerintah di Bima,Sumbawa Timur (hal. 163 – 188). Dalam:Michael R. Dove (ed). (1985). PerananKebudayaan Tradi-sional Indonesia dalamModernisasi. Jakarta: Yayasan OborIndonesia.
Chamala, S and P.M. Shingi. 2007. Chapter 21 -Establishing and Strengthening FarmerOrganizations. FAO. http://www.fao.org/docrep/W5830E/w5830e0n.htm.
Chambers, Rt. 1987. Pembangunan Desa: Mulaidari Belakang. Jakarta: LP3ES.
Dimaggio, P. J. and W.W. Powell. 1991. The NewInstitutionalism In Organizational Analysis.Chicago: University of Chicago Press.
Fafchamps, M. 2007. Global Poverty ResearchGroup. 2007. Trade and Social Capital.http://www.gprg.org/themes/ t4-soccap-pub-socsafe/sc-uses/trade-sc.htm, 20agustus 2007
Fauzi, N. 1999. Petani dan Penguasa: DinamikaPerjalanan Politik Agraria Indonesia.Yogyakarta: Insist Press, KPA, danPustaka Pelajar.
Granovetter, M. 2005. The Impact of SocialStructure on Economic. Journal ofEconomic Perspective 19(1): 33–50.
Grootaert, C and T. van Bastelaer. 2001.Understanding and Measuring SocialCapital: A Synthesis of Findings andRecommendations from the Social CapitalInitiative. Social Capital Initiative WorkingPaper No. 24. Washington, D.C: The WorldBank.
Hayami, Y dan T. Kawagoe. 1993. The AgrarianOrigins of Commerce and Industry: AStudy of Peasant Marketing In Indonesia.St. Martin's Press. Singapore.
Hellin, J., M. Lundy, and M. Meijer. 2007. FarmerOrganization, Collective Action and MarketAccess in Meso-America. Capri WorkingPaper No. 67, October 2007. ResearchWorkshop on Collective Action and MarketAccess for Smallholders. October 2-5,2006 - Cali, Colombia. International FoodPolicy Research Institute (IFPRI),Washington.
Hutahaean, L., R.H. Anasiru, dan I.G.P. Sarasutha.2010. Analisis Kelayakan UsahaPelayanan Jasa Alsintan di SulawesiTengah. Laporan Penelitian. BalaiPenelitian dan Pengkajian TeknologiPertanian, Badan Litbang Pertanian,Jakarta.
Jackson, K.D. and L.W. Pye (eds). 1978. PoliticalPower and Communications in Indonesia.University of California Press. Berkeley,LA, and London.
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/Kpts/OT.210/3/1997 tentang PedomanPembinaan Kelompok Tani-Nelayan.
Koentjaraningrat. 1974. Pengantar Antropo-logi.Jakarta: Penerbit Aksara Baru.
Lema, N.M. and B.W. Kapange. 2006. Farmers’Organization and Agriculture Innovation inTanzania. Dalam: www.kit.nl
Lipton, M. 1977. Why Poor People Stay Poor: AStudy Of Urban Bias In WorldDevelopment. Harvard University Press,1977 - 467 pages
Lobo, C. 2008. Institutional And OrganizationalAnalysis For Pro-Poor Change: MeetingIFAD’s Millennium Challenge. Asourcebook. Rome: IFAD.www.ifad.org/english/institutions/sourcebook.pdf. 8 Januari 2013.

144
FORUM PENELITIAN AGRO EKONOMI, Volume 30 No. 2, Desember 2012 : 129 -145
March, J.G. and J.P. Olsen. 1984. The NewInstitutionalism: Organizational Factors inPolitical Life. American Political ScienceReview 78 (3): 734-749.
Martinussen, J. 1997. Society, State, & Market: AGuide To Competing Theories ofDevelopment. Danish Association forInternational Co-operation. Copenhagen.
Nee, V. 2005. The New Institutionalism inEconomics and Sociology. In: TheHandbook of Economic Sociology. 2nd ed.Niel J. Smelser dan Richard Swedberg(eds.) Princeton University Press.
Nordholt, N.S. 1987. Ojo Dumeh: KepemimpinanLokal dalam Pembangunan. Pustaka SinarHarapan. Jakarta.
North, DC. 2005. Institutional Economics.http://nobelprize.org/economics/laureates/1993/north-lecture.html, 27 April2005.
Nurmanaf, R., E.L. Hastuti, H. Tarigan, dan Supadi.2033. Pemberdayaan Kelem-bagaanTradisional Ketenagakerjaan Pertanian diPedesaan dalam Upaya PengentasanKemiskinan. Laporan Penelitian. PusatPenelitian dan Pengembangan SosialEkonomi Pertanian, Bogor. 171 hal.
Pakpahan, A. 2004. Mengapa Kita Tertinggal?Karena Kita Lalai akan Dinamika danKekuatan Rakyat. Majalah AnalisisKebijakan Pertanian (Agricultural PolicyAnalysis). Pusat Penelitian danPengembangan Sosial Ekonomi Pertanian,Bogor. Hal 101-118.
Peraturan Menteri Pertanian No. 273/Kpts/Ot.160/4/2007 Tentang PedomanPenumbuhan dan PengembanganKelompoktani dan GabunganKelompoktani.
Perera, J. 2004. Farmer’s Behaviour in RiceIrrigation in Monsoon Asia: Facts andFallacies. South Asia Economic Journal.5/145, 2004.
Portes, A. 2006. Institutions and Development: AConceptual Reanalysis. Population andDevelopment Review 32 (2): 233–262.
Putra, HAS. 1988. Minawang: Hubungan Patron-Klien Di Sulawesi Selatan. Gadjah MadaUniversity Press.
Robbins, L. 2005. Understanding Institutions:Institutional Persistence and Institu-tionalChange. (http://www.lse.ac.uk/collections/LSEPublicLecturesAndEvents/events/2004/20031222t0946z001. htm., 27April 2005).
Saptana, T. Pranadji, Syahyuti, dan RoosgandaE.M. 2003. Transformasi Kelembagaanuntuk Mendukung Ekonomi Kerakyatan diPedesaan. Laporan Penelitian. PSE,Bogor.
Scott, J.C. 1993. Perlawanan Kaum Tani. YayasanObor Indonesia, Jakarta. 384 hal.
Scott, R.W. 1995. Institutions and OrganizationsFoundations for Organizational Science:Foundations for Organizational Science. ASage Publications Series. Sage Publica-tions, Inc.
Scott, R.W. 2008. Institutions and Organizations:Ideas an Interest. Los Angeles, London,New Delhi, Singapore: Sage Publication.Third Edition. 266 hal.
Shanin, T. 1990. Defining Peasants: EssaysConcerning Rural Societies, ExpolaryEconomies, and Learning from them in theContemporary World. Top of Form Oxford,UK and Cambridge, MA, USA.
Stockbridge, M., A. Dorward, and J. Kydd. 2003.Farmer Organizations for Market Access: ABriefing Paper. Wye Campus, Kent,England: Imperial College, London.
Syahyuti. 1998. Beberapa Karakteristik dan PerilakuPedagang Pemasaran Komoditas Hasil-Hasil Pertanian di Indonesia. Forum AgroEkonomi Vol. 16 No.1, Juli 1998.
Syahyuti. 2002. Pembentukan Struktur Agraria padaMasyarakat Pinggiran Hutan. Tesis padaJurusan Sosiologi Pedesaan. IPB, Bogor.
Syahyuti. 2010. Lembaga dan Organisasi PetaniDalam Pengaruh Negara Dan PasarMajalah Forum Agro Ekonomi Vol. 28 No.1Tahun 2010. Pusat Sosial Ekonomi danKebijakan Pertanian, Bogor.
Syahyuti. 2012. Pengorganisasian Diri PetaniDalam Menjalankan Agribisnis DiPedesaan: Studi Lembaga Dan OrganisasiPetani Dalam Pengaruh Negara DanPasar. Disertasi Universitas Indonesia,Depok.
Teken, I B. l988. Irigasi Subak di Bali. dalam Irigasi,Kelembagaan dan Ekonomi, Jilid II,Gramedia, Jakarta).
Temple, G.P. 1976. Mundurnya Involusi Pertanian:Migrasi, Kerja dan Pembagian Pendapatandi Pedesaan Jawa. Prisma No. 3 April1976.
Tjondronegoro, S.M.P. 1984. Social Organi-zationand Planned Development in Rural Java: AStudy of the Organizational Phenomenonin Kecamatan Cibadak, West Java and

145
PENGORGANISASIAN SECARA PERSONAL DAN GEJALA INDIVIDUALISASI ORGANISASI SEBAGAI KARAKTER UTAMAPENGORGANISASIAN DIRI PETANI DI INDONESIA Syahyuti
Kecamatan Kendal, Central Java,Singapore: Oxford University Press.
Tjondronegoro, SMP dan G. Wiradi. (Eds). 1984.Dua Abad Penguasaan Tanah. PenerbitGramedia, Jakarta. 344 halaman
Undang-Undang No. 16 tahun 2006 tentang SistemPenyuluhan Pertanian, Perikanan danKehutanan
Wahono, Francis. 1994. Dinamika Ekonomi SosialDesa Sesudah 25 Tahun Revolusi Hijau.(pp. 3-21) Majalah Prisma No. 3 Maret1994.
White, B. 1997. Agroindustry And Contract FarmersIn Upland West Java. Journal of PeasantStudies. Volume 24, Issue 3, 1997.
Wijayaratna, C. M. 1993. Impacts of the InstitutionalSystem on the Participants and onIrrigation Performance: A Note for
Discussion. In Charles L. Abernethy (ed).The Institutional Framework for Irrigation.Proceedings ofa Workshop Chiang Mai,Thailand. 1-5 November, 1993. GermanFoundation For International DevelopmentInternational Irrigation ManagementInstitute Royal Irrigation Department OfThailand
Wijayaratna, C.M. 2002. Role of LocalCommunication and Institution inIntegrated Rural Development. APOSeminar, Asian Productivity Organization.2004.
World Bank. 2008. World Development Report2008: Agriculture for Development. WorlBank, US. http://econ.worldbank. org/