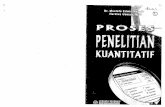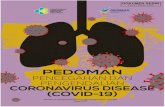I PENCEGAHAN DAN PE~ BERANTASAN
Transcript of I PENCEGAHAN DAN PE~ BERANTASAN
NASKAH AKAOEMIK I
RANCANGAN iUNDA~1G-UNDANG
TEINTANG I
PENCEGAHAN DAN PE~1BERANTASAN '
KOMISI IV; i
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ~EPUBLIK INDO:NESIA I
SEPliEMBER 2008 I
I
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemoerantasan Pembal'C!kan Liar-2008
BAB I.
BAB II.
BAB Ill.
BABIV ..
BABV.
DAFTARISI
PENDAHULUAN Halaman
A
B.
c. D.
Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ldentifikasi Masalah .................................................... 9
Tujuan dan Kegunaan
Metode Pendekatan
LANDASAN PEMIKIRAN
........................................... 9
. .......................................... 10
A Landasan Filosofis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
B. Landasan Sosiologis .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. 13
C. Landasan Yuridis .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . .. . .. 15
KERANGKA KONSEPTUAL
A Teori Pembentukan Hukum .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . 29
B. Pengertian Pembalakan Liar (Illegal Logging) ··············· 30
C. Pembalakan Liar Sebagai Tindak Pidana .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 38
D. Upaya Mengatasi Pembalakan Liar .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 50
RUANG LINGKUP NASKAH AKADEMIK
A Materi Muatan Rancangan Undang-Undang . . . . . . . . . . . . . . . 55
B. Usulan Sistematika RUU .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. 72
PENUTUP
A Kesimpulan ............................................................ 74
B. Saran ..................................................................... 75
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan liar-2008
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN (KONSEP AWAL DRAFT RUU)
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
A. Latar Belakang
BABI
PENDAHULUAIN
Tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan
makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 33 ayat (3)
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan salah satu kekayaan
alam Indonesia yang dengan berbagai fungsinya sangat panting bagi kehidupan
manusia. Oleh karenanya dalam pemanfaatannya harus dilakukan secara
terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan
daya dukungnya, serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan
keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan
pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, yang diarahkan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat di masa kini dan di masa mendatang sebagaimana ketentuan
dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Hutan Indonesia merupakan contoh hutan tropis yang paling lengkap,
beragam, dan bernilai di dunia 1• Hutan-hutan ini tidak hanya berfungsi sebagai
habitat untuk berbagai flora dan fauna, namun juga memainkan peranan panting
dalam mendukung perkembangan ekonomi kehidupan masyarakat terutama di
wilayah pedesaan dan pelayanan jasa lingkungan. Namun hutan Indonesia telah
dieksploitasi tanpa mempertahankan aspek pelestariannya.
1 Statistik mengenai tutupan hutan Indonesia saat ini sangat bervariasi tetapi berkisar antara 100 juta sampai 124 juta hektar. Data Departemen Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia mempuny;ai sekitar 104 juta hektar hutan pada tahun 2000, sedangkan Kelompok Kerja Masa Depan Hutan NRMBappenas memperkirakan bahwa hutan, termasuk perkebunan meliputi kira-kira 123 juta hektar. Sektor kehutanan secara kumulatif menghasilkan US$6,5 milyar pendapatan bagi Pemerintah Indonesia antara tahun 1985 dan 2002 (Bank Dunia 2006).
1
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
Pemanfaatan dan pengelolaan sektor kehutanan dalam perkembangannya
menjadi salah satu bagian terpenting dalam pengelolaan lingkungan hidup qan
menjadi sorotan bukan hanya secara nasional akan tetapi menjadi wacana global.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa I
Bangsa di Rio de Jeneiro tahun 1992 yang menghasilkan suatu konferensi tenta:ng
beberapa bidang penting diantaranya tentang prinsip-prinsip kehutanan (for~st
principle) yang dituangkan dalam dokumen perjanjian: "Non-Legally Binding
Authorative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management,
Conservation and Suistainable Development of all types of Foresf'. Prinsip tentang
kehutaan ini kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Kehutanan Indonesia,
yaitu UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan2•
Salah satu masalah yang sangat krusial dalam bidang lingkungan hidup pada
sektor kehutanan ini adalah masalah pembalakan liar (illegal logging). Steven
Devenish, Ketua Misi Forest Law Enforcement and Trade (FLEGT) dari Uni Eropa
menyatakan bahwa pembalakan liar adalah penyebab utama kerusakan hutan di
Indonesia dan menjadi masalah serius di dunia. Hal ini menjadi perhatian Uni Eropa
dalam sepuluh tahun terakhir dan akhirnya memberikan bantuan dalam rangka
pencegahan pembalakan liar tersebut3.
World Bank sejak awal tahun 1980-an sudah memberi peringatan bahwa
hutan dunia yang hanya tinggal di tiga negara yaitu Indonesia, Brazil dan Zaire
supaya dijaga ketat kelestariannya. World Bank pada Juni 2004 lalu menyatakan
bahwa setiap detik pohon-pohon hutan Indonesia ditebangi secara liar. Per
menitnya mencapai 6 kali luas lapangan bola dan kerugian per tahun mencapai 31
(tiga puluh satu) triliun rupiah. World Bank mencatat, sebelum era reformasi
kerusakan hutan tidak mencapai jutaan hektar per tahun, sedangkan di era
reformasi justru rata-rata kerusakan hutan mencapai 3,8 juta hektar per tahun.
Tahun 2004, kerusakan hutan Indonesia sudah hampir 45 juta hektar dari luas hutan
2 Koesnadi Hardjasumantri, Hukum Tata Lingkungan,Cet. Ke-17, edisi ke-7,Gadjah Mada University Press-Yogyakarta, 1999, hal. 19. 3 Harian Kompas, 19 Agustus 2003, hal.1.
2
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
yang hanya tinggal 120,35 juta hektar. Dengan demikian lebih dari sepertiga hutan
tropis Indonesia telah hancur4.
Salah satu penyebab degradasi sumber daya hutan Indonesia adalah adanya
praktek pembalakan liar. Pembalakan liar mencakup pelanggaran hukum yang
berakibat pada eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan dan mengarah
kepada penggundulan dan perusakan hutan. Pelanggaran-pelanggaran ini bisa
terjadi pada setiap tahapan produksi kayu, seperti pada penebangan kayu,
pengangkutan bahan mentah, pengolahan dan perdagangan, bahkan melibatkan
cara-cara yang tidak sah untuk mendapatkan akses ke dalam hutan, melanggar
aturan kepabeanan, melanggar administratif keuangan seperti menghindari
pembayaran pajak dan pencucian uang. Pelanggaran dapat juga terjadi karena
kebanyakan wilayah-wilayah administratif dari lahan hutan negara dan kebanyakan
dari unit-unit produksi resmi yang beroperasi di dalamnya tidak dipisah dari
keterlibatan dengan masyarakat lokal yang sesungguhnya sangat diperlukan.
Jika dilkelompokkan paling tidak ada 3 jenis pembalakan liar yang telah
merusak hutan Indonesia. Pertama, pembalakan yang dilakukan oleh operator yang
legal secara teknis administratif sebagai contoh oleh pemilik Hak Pengusahaan
Hutan atau Hutan Tanaman lndustri atau perkebunan namun dalam prakteknya
telah melanggar persyaratan ketentuan dalam HPH karena kelebihan menebang di
hutan industri atau mengambil kayu pada areal konseNasi yang dilindungi.
Operator-operator ini diberikan ijin untuk menebang pohon secara selektif. 5 Hal ini
4 Anton Tabah, "Mengurai Anatomi Illegal Logging Dan Deforestasi Di Indonesia", Makalah pada Seminar Nasional di Manggala Wana Bhakti, Jakarta, 16 Mei 2005, hal 1.
5 Analisis manajemen kehutanan (baca Sist, Plinio, Timothy Nolan, Jean-Guy Bertault, and Dennis Dykstra. 1998. "Harvesting Intensity versus Sustainability in Indonesia." In Forest Ecology and Management 108 (3): 251-60 dan Sist, Plinio, Robert Fimbel, Douglas Sheil, Robert Nasi, and MarieHelene Chevallier. 2003. "Towards Sustainable Management of Mixed Dipterocarp Forests of Southeast Asia: Moving beyond Minimum Diameter Cutting Limits." Environmental Conservation 30 (4): 364-74) telah memberikan catatan bahwa Sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia secara efektif telah mengurangi pengelolaan hutan lestari karena mengijinkan pohon-pohon dengan diameter 50 - 60 meter untuk ditebang dalam jangka waktu penebangan 35 tahun dan mensyaratkan pembersihan tumbuhan labisan bawah, Penelitian ilmiah baru, mengindikasikan bahwa jangka waktu penebangan seharusnya minimal 40-60 tahun dan tidak lebih dari 8 pohon per hektar boleh ditebang dari areal hutan untuk memungkinkan regenerasi hutan lestari.
3
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan don Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
berakibat pada meluasnya kerusakan hutan, pada kasus tertentu dapat terjadi
penggundulan hutan. Beberapa dari praktek-praktek serupa masih terus berlanjut
sampai sekarang.
Kedua, pembalakan liar yang dilakukan berdasarkan ijin HPH yang diperoleh
secara tidak sah yang diterbitkan oleh pejabat pemerintahan daerah dan biasanya
berlaku selama 1 (satu) tahun. Praktek ini teiah disahkan pada tahun 1999, namun
dicabut kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002.6 (sebagai
peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan). Pembalakan jenis ini mengakibatkan hutan menjadi gundul dan
kerusakan hutan karena ijin menebang yang diterbitkan oleh pejabat pemerintahan
daerah sering berlokasi di dalam hutan sekunder yang telah ditebang, contohnya di
dalam konsesi HPH aktif dan non aktif. Lebih jauh lagi, operasi pembalakan
semacam ini jarang diatur dan tidak mengikuti tata cara penebangan yang selektif.
Kebanyakan hanya ingin mengeksploitasi sumber daya tersebut.
Ketiga, pencurian kayu atau sering disebut sebagai penebangan liar. Jenis
pembalakan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang-orang setempat yang
dikoordinir oleh cukong kayu dan pedagang perantara untuk secara selektif
menebang pohon-pohon yang memiliki nilai ekonomis tinggi di hutan produksi, hutan
lindung, maupun di kawasan yang dilindungi. Orang-orang ini tidak memiliki hak ijin
yang sah dari pemerintah untuk menebang pohon.
Dalam beberapa tahun terakhir pembalakan liar sudah semakin meluas dan
kompleks. Pembalakan liar tidak hanya terjadi di hutan produksi, tetapi juga telah
merambah ke hutan konversi, hutan lindung, dan hutan konservasi sehingga
menyebabkan menurunnya kepercayaan dan martabat Indonesia di mata dunia
internasional. Pembalakan liar juga telah berkembang menjadi suatu tindak pidana
di bidang kehutanan yang berkembang secara meluas, lebih terorganisir, melibatkan
banyak pihak, baik dalam skala nasional maupun internasional. Hal ini terbukti dari
6 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 pada tahun 2007 dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 yang juga melarang pejabat pemerintah kabupaten mengeluarkan IUPHHK dari hutan produksi walau tetap mengijinkan bupati atau walikota mengeluarkan IUPK kepada perseorangan dan koperasi yang ingin memanfaatkan kayu bagi keperluan pribadi. Kayu yang diambil dengan izin itu tidak boleh diperdagangkan secara komersial.
4
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan don Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
ketidakmampuan hukum menjerat aktor ilegall loging. Pembalakan liar tidak lagi
mumi berdiri sendiri namun telah terbangun kerjasama yang merambah ke praktek
perdagangan kayu illegal (illegal timber trade) yang melibatkan komunitas negara
luar. Struktur organisasi dan modus operandi yang umum terjadi dalam pembalakan
liar adalah terorganisasinya dengan rapi dan profesional seluruh pelaksanaan di
lapangan sehingga sering kali sulit bagi perangkat hukum untuk dapat menangkap
para "cukong" sebagai akibat dari sistem serta pranata hukum positif yang ada.
Data statistik tingkat pembalakan liar yang sesungguhnya terjadi di Indonesia
tidak diketahui secara jelas. Namun ada beberapa penulis yang mencoba
menganalisa tingkat pembalakan liar di Indonesia dengan menggunakan analisis
statistik yang dikombinasikan dengan analisa kehilangan tutupan hutan (lihat tabel
1).
Tabel 1. Perkiraan mengenai besarnya ting1kat pembalakan liar
Analis Ta- Konsumsi Perkiraan Penebang Penebanga hun lndustri Penebanga an ilegal n llegal
m3 n legal m3 m3 % (Konsumsi
-Penebang an legal)
Tacconi, 2001 56 10 46 82 Obidzinski and Agung (2004)
Brown (2002a) 2000 73 17 56 76
NRM-MFP- 2004 53 17 38 68 Bappenas Forest Futures Working Group (2004)
Palmer (2000) 1997 108 43 65 60
Scotland (1999) 1998 84 52 32 38
BRIK (2003)* 2003 42 42 0 0
MoF (2004)* 2003 42 42 0 0
* hanya ekspor
5
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
Masing-masing penulis memberikan perkiraan yang berbeda-beda, namun
secara kasar, kurang lebih 50 juta meter kubik kayu telah diambil, diolah,
diperdagangkan dan dikonsumsi secara ilegal dari tahun 2002 sampai tahun 2003.
Sebagian besar dari kayu itu berasal dari hutan produksi (27 juta meter kubik), dari
hutan konversi (12 juta meter kubik), dari hutan lindung (7 juta meter kubik), dan dari
hutan konservasi (4 juta meter kubik). Kira-kira 80 % (40 juta meter kubik) diproses
di Indonesia guna memproduksi kurang lebih 17 juta meter kubik bubur kayu, 13 juta
meter kubik kayu lapis dan papan balok, dan 10 juta meter kkubik kayu gergajian.
Sisanya (10 juta meter kubik) diperdagangkan dan diekspor secara ilegal dalam
bentuk kayu bulat. Kayu bulat ini diperkirakan diekspor ke Malaysia dan Cina,
sementara produk kayu olahan diperkirakan dikonsumsi di Indonesia (17 juta meter
kubik), Cina (6 juta kubik), Singapura, Korea, dan Taiwan (6 juta meter kubik),
Jepang (5 juta meter kubik), AS dan Kanada (3 juta meter kubik), Uni Eropa (2 juta
meter kubik). Kayu-kayu yang diekspor ke Cina, Singapura, Korea, Taiwan dan
Jepang diperkirakan diolah ulang dan ekspor ulang ke AS dan UE.
Dalam perspektif pengusaha legal, kegiatan pembalakan liar dan
perdagangan kayu illegal (illegal timber trade) sangatlah merugikan, karena
berdampak pada langka dan mahalnya memperoleh bahan baku kayu, sementara
negara luar sebagai kompetitor seperti Malaysia dan China dengan mudahnya
memperoleh bahan baku kayu sehingga dengan leluasa merebut pasar yang dahulu
dipegang oleh pengusaha Indonesia. Melalui kegiatan pembalakan liar di Indonesia,
mereka telah merebut sekaligus menguasai pasar dunia.
Dengan mempelajari kekurangan peraturan perundang-undangan yang ada
dan lemahnya penegakan hukum dalam kegiatan pembalakan liar, beberapa negara
lain pada waktu yang sama memanfaatkan momentum tersebut dengan menikmati
pertumbuhan pusat industri perkayuan maupun kegiatan trading di negaranya,
negara-negara tersebut antara lain Malaysia, Singapura dan Amerika Serikat.
Sementara itu, bagi masyarakat yang hidup di sekitar hutan, mereka yang
pertama akan terkena dampaknya akibat pembalakan liar. Meskipun terkadang
6
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan liar-2008
mereka ikut terlibat dalam pembalakan liar, karena faktor ekonomi.7 Dari
pembalakan liar, mereka hanya menikmati keuntungan kecil yang sifatnya
sementara, dan pada akhirnya ketika hutan habis dan lingkungannya semakin
rusak, mereka pun akan terancam kehidupan sosial ekonominya. Mereka adal1ah
kelompok yang paling rentan terhadap dampak buruk yang ditimbulkan oleh proses
penggundulan hutan.
Praktek pembalakan liar yang telah merongrong kelestarian hutan dan
keseimbangan ekologi dunia merupakan bentuk kejahatan pidana yang harus
dituntaskan. Dampaknya sangat dahsyat terhadap kelangsungan fungsi hutan
penyangga ekosistem bumi secara lintas teritori dan lintas generasi. Dengan
demikian kegiatan pembalakan liar juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan
terorisme, karena adanya beberapa kesamaan ciri, yaitu :
a. termasuk kejahatan pidana;
b. berlangsung lintas negara;
c. terorganisir secara sistematis;
d. memiliki jaringan (network) yang luas;
e. mengancam keselamatan hidup umat manusia di seluruh dunia secara
lintas generasi.
Melihat perkembangan modus operandi dan locus pembalakan liar yang
semakin berkembang dan berlangsung di seluruh fungsi kawasan, maka
penanganannya harus melibatkan seluruh pihak. Untuk itu perlu adanya persamaan
persepsi dan pemahaman yang sama dari seluruh aparat penegak hukum, mulai
dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang Pengadilan.
Pembalakan liar merupakan perbuatan melanggar hukum yang jika dilihat
dari aspek lingkungan mengakibatkan rusaknya kelestarian hutan yang selanjutnya
7 Berdasarkan beberapa penelitian, keterlibatan masyarakat pedesaan yang bergantung pada hutan dengan pembalakan liar terjadi karena antara lain, hukum yang ada hanya mengakomodasi sebagic:m dari penghidupan mereka dan hak-hak mereka, adanya kerancuan dan ketidakpastian hukum, hukurn yang lebih mementingkan kepentingan pengusaha berskala besar atau badan pemerintah yang diberikan prioritas dibandingkan dengan hukum yang menjamin kepentingan masyarakat, dan kondisi kemiskinan serta tidak adanya pilihan lain untuk mencari penghidupan. Baca Colchester, M. et.al, 2006, Justice in the Forest: Rural Livelihoods and Forest Law Enforcement, Bogar, Indonesia: Center for lnternasional Forestry Research.
7
f'laskah Akademik RUU tentang Pencegahan don Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
akan menimbulkan bencana alam yang lebih dahsyat seperti tanah longsor dan
banjir di musim hujan atau kekeringan dan kebakaran hutan di musim kemarau.
Selain itu, rusaknya hutan Indonesia juga menyumbang pemanasan gloQal.
Sedangkan jika dilihat dari aspek ekonomi, pembalakan liar mengakibatkan kerugian
negara karena hilangnya potensi hasil hutan dan tidak terpungutnya Provisi Sumber
Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
Kerugian dari aspek ekonomi tersebut berpengaruh negatif terhadap usaha
pengelolaan hutan alam resmi dan industri kayu pertukangan (non pulp dan kertas),
karena sebagian besar kegiatan pembalakan liar dan penyelundupan kayu adalah
berasal dari hutan alam. Perlu diperhatikan bahwa kelebihan industri kehutanan
Indonesia adalah dari sisi bahan baku, sedangkan dari sisi lainnya (SOM,
infrastruktur, teknologi, fiskal/pungutan, dan birokrasi) Indonesia masih tertinggal jika
dibandingkan dengan negara-negara pesaing8.
Selama ini terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
pembalakan liar, namun dalam implementasinya belum efektif dilaksanakan.
Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, semakin memperburuk
kegiatan pembalakan liar. Koordinasi antara penegak hukum (polisi dan PPNS
sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut dan hakim sebagai eksekutor vonis)
dalam realitanya belum berjalan optimal, bahkan seringkali terjadi kesalahan
interpretasi antara jaksa penuntut umum dan penyidik terhadap pasal-pasal yang
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selain
itu penjatuhan vonis terhadap pelaku pembalakan liar sering tidak proporsional atau
terlalu ringan dan tidak sepadan dengan bobot kejahatannya. Hal tersebut sering
dijadikan dasar acuan para pelaku kegiatan pembalakan liar untuk lebih berani lagi
dalam melakukan perbuatan kejahatan pembalakan liar.
Rancangan Undang-Undang ini juga ditujukan untuk memberikan kepastian
hukum bagi upaya pencegahan pembalakan liar, karena pembalakan liar tidak
hanya bisa diatasi dengan upaya penegakan hukum saja tetapi juga harus
8 Nana Suparna, "Illegal Logging Dari Sisi Sistem Pengelolaan Hutan': Makalah yang disampaik~n dalam Seminar Nasional mengenai Illegal Logging, Permasalahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia Didekati dari Aspek Hukum, Ekonomi, dan Manajemen, Jakarta, 16 Mei 2005, hal. 2.
8
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
dengan upaya-upaya pencegahannya. Berdasarkan uraian tersebut maka perlu
disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan
liar.
B. ldentifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang akan
menjadi pembahasan dalam naskah akademik ini yaitu:
1. Bagaimana upaya yang komprehensif dalam rangka melakukan pencegahan dan
pemberantasan pembalakan liar di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk kelembagaan yang tepat sebagai penanggungjawab
pelaksanaan upaya pencegahan dan pembalakan liar secara nasional?
3. Bagaimana bentuk pengaturan sanksi yang efektif guna memberikan daya paksa
terhadap penegakan hukum dalam pemberantasan pembalakan liar?
C. Tujuan dan Kegunaan
Tujuan dari naskah akademik ini adalah:
1. memberikan arahan perumusan materi muatan mengenai upaya pencegahan
dan pemberantasan pembalakan liar secara komprehensif dalam penyusunan
dan pembentukan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Pembalakan liar.
2. mengformulasikan bentuk kelembagaan yang tepat dengan kewenangan yang
jelas dan tegas sebagai penanggungjawab pelaksanaan pencegahan dan
pemberantasan pembalakan liar secara nacional
3. mengformulasikan bentuk sanksi yang efektif guna memberikan daya paksa dan
efek jera dalam penegakan hukum pemberantasan pembalakan liar.
9
.Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan don Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
Kegunaan praktis dari naskah akademis ini adalah sebagai dasar acuan yang
bersifat ilmiah dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar.
D. Metode Pendekatan
Metode Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini
adalah melalui kajian literatur dan penelitian empiris. studi kepustakaan dilakukan
dengan mengkaji bahan-bahan serta data-data yang berkaitan dengan pembalakan
liar, jenis-jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Data
sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum
primer berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder
berupa buku-buku, artikel, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah
lainnya. Bahan hukum tersier seperti: kamus, buku pegangan, almanak dan
sebagainya, yang semuanya dapat disebut bahan referensi atau bahan acuan atau
rujukan.
Selain itu juga dilakukan inventarisasi serta harmonisasi peraturan
perundang-undangan yang berkaitan atau berhubungan dengan pembalakan liar.
Selain lebih menekankan metode kepustakaan atau normatif, juga dilakukan metode
empiris, yaitu melalui penelitian lapangan ke daerah yang terdapat praktek
pembalakan liar yang marak yaitu Provinsi Kalimantan Barat (Pontianak), Provinsi
Riau (Kabupaten Kampar). Hal tersebut dilakukan untuk mendukung data yang di
peroleh dari data sekunder atau kepustakaan dan mendapatkan informasi dari pakar
atau ahli yang berkompeten dalam kaitannya dengan pembalakan liar.
Penelitian empiris dilakukan dengan meneliti bagaimana penerapan aturan
aturan yang berkaitan dengan penanggulangan pembalakan liar diterapkan di
masyarakat. Penelitian dilakukan dengan meneliti ketentuan-ketentuan yang ada di
dalam peraturan perundangan serta peraturan pelaksanaannya untuk mengetahui
10
.. Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan don Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
latar belakang dan tujuan berbagai pengaturan yang berlaku mengenai pembalakan
liar. Hasil penelitian tersebut .adalah berupa hasil wawancara dengan beberapa
informan, yaitu pejabat pemerintah, aparat kepolisian, aparat kejaksaan, dan
anggota masyarakat yang terkait dengan praktek pembalakan liar.
Selanjutnya data-data yang diperoleh baik melalui penelusuran kepustakaan
maupun penelitian lapangan tersebut dianalisa secara yuridis normatif. Sebagai
suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap
norma hukum yakni hukum dalam arti law as it is written in the books (dalam
peraturan perundang-undangan)9. Dengan demikian obyek yang dianalisis adalah
norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Artinya data kepustakaan dan
hasil wawancara dianalisis secara mendalam, holistik dan komprehensif.
Penggunaan metode analisis secara kualitatif didasarkan pada pertimbangan, yaitu
pertama data yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda
antara satu dengan yang lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan. Kedua,
sifat dasar data yang dianalisis adalah menyeluruh (comprehensif) dan merupakan
satu kesatuan yang bulat (holistic). Hal ini ditandai dengan keanekaraaman datanya
serta memerlukan informasi yang mendalam (indepth information) 10.
9 Ronald Dworkin, Legal Research, (Daedalus: Spring, 1973),h.250 1° Chai Padhista, "Theorical,Terminological, and Philosophical Issue in Qualitative Research", dalam Attig.et.al, A Field Manusal an Selected Qualitative Research Methods, (Thailand: Institute for Population and Social Research, Mah idol University, 1991) hal. 7.
11
, Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan don Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
BAB II
LANDASAN PEMIKIRAN
A. Landasan Filosofis
Hutan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang tak ternilai harganya
yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Selama
tiga dekade terakhir, hutan telah menjadi modal utama pembangunan ekonomi
nasional, yang memberi dampak positif antara lain terhadap peningkatan devisa,
penyerapan tenaga kerja dan mendorong pengembangan wilayah dan
pertumbuhan ekonomi. Bagi pemerintah, hutan memberikan manfaat berupa
penerimaan pemerintah dari pungutan Dana Reboisasi (DR), Bunga Jasa Giro
DR, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), luran Hak Pengusahaan Hutan
Tanaman lndustri, luran Hak Pengusahaan Hutan, Ekspor Satwa Liar, Denda
Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam dan luran
Usaha Pariwisata Alam. Bagi pihak swasta, hutan merupakan sumber daya yang
memberi keuntungan ekonomi yang tinggi bagi usaha mereka. Dan bagi
masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan, hutan adalah mata
pencaharian untuk kehidupan mereka.
Selain manfaat ekonomi, hutan juga memberikan manfaat ekologi bagi
kehidupan manusia. Keberadaan hutan seba,gai bagian dari sebuah ekosistetn
yang besar memiliki arti dan peran penting dalam menyangga sistem kehidupan.
Berbagai manfaat dapat diperoleh dari keberadaan hutan melalui fungsinya, baik
sebagai penyedia sumber daya air bagi manusia dan lingkungan, kemampu~n
penyerapan karbon, pemasok oksigen di udara, penyedia jasa wisata, dan
mengatur iklim global.
Hutan juga memberikan manfaat sosial budaya bagi kehidupan manusia.
Bagi masyarakat desa hutan, hutan adalah kehidupan mereka, yaitu tempat
dimana mereka tinggal, hidup, dan berinteraksi dengan anggota masyarakat 12
.f:Jaskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
lainnya. Mereka mempunyai hubungan religi dan hubungan kemasyarakatan
dengan hutannya.
Begitu banyak manfaat yang kita peroleh dari hutan. Pasal 33 ayat (3)
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi dan
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karenanya,
hutan dengan berbagai fungsinya harus dimanfaatkan secara terencana, rasional,
optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukungnya,
serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan
hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang
berkelanjutan. Pembalakan liar adalah bentuk penyimpangan dari pemanfaatan
hutan yang seharusnya. Akibat pembalakan liar, hutan tidak lagi dapat
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
B. Landasan Sosiologis
Hutan sebagai bagian ekosistem memiliki peran sebagai penyangga
keseimbangan ekologi dan kehidupan manusia. Pembalakan liar menjadi
ancaman kepunahan fungsi ekologi hutan tropis Indonesia. Menurut perhitungan
terakhir, kerusakan hutan Indonesia pada tahun 2000 -2005 adalah 1,8 - 2 juta
hektar per tahun. lni adalah angka tertinggi di dunia. Berdasarkan data itu,
potensi gas rumah kaca yang dilepaskan Indonesia setiap tahun mencapai 93,6
- 280,7 juta ton karbon. Sementara itu, reboisasi dan penghijauan kembali yang
berlangsung selama ini melalui Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(GERHAN) dapat dikatakan gagal. Berdasarkan data yang ada, realisasi
keberhasilan GERHAN 2003-2007 rata-rata hanya mencapai 250.000 hektare
per tahun. Tingginya potensi gas rumah kaca yang dilepaskan Indonesia
tersebut memberi sumbangan meningkatnya pemanasan global. Pemanasan
global dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim, yang nantinya akan
13
,Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
memberikan konsekuensi berat bagi ketersediaan air dan munculnya banjir di
daerah-daerah tropis seperti di Indonesia. Hal tersebut tentunya melanggar hak
asasi manusia, yaitu hak untuk hidup.
Pembalakan liar yang terjadi di Indonesia menimbulkan dampak yang
sangat luas terhadap kondisi lingkungan sekaligus kelangsungan fungsinya bagi
kehidupan berbagai komunitas secara lintas generasi. Ancaman kekeringan,
bahaya banjir, tanah longsor, kebakaran, menipisnya lapisan ozon, pemanasan
global dan perubahan iklim menjadi ancaman bagi keberlangsungan dan
keberlanjutan kehidupan umat manusia. Lebih jauh, sewaktu-waktu akan terjadi
bencana alam yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan hilangnya harta
benda. Masyarakat selalu dihantui oleh kecemasan sebagai akibat rusaknya
lingkungan yang akan mengakibatkan timbulnya berbagai bencana alam.
Dengan demikian pembalakan liar merupakan salah satu bentuk pelanggaran
terhadap hak asasi manusia.
Selain itu dari sisi ekonomi, pembalakan liar yang terjadi telah
menyebabkan kerugian dalam keuangan negara, yaitu mengurangi penerimaan
devisa negara dan pendapatan negara. Selain itu pembalakan liar juga
mengakibatkan timbulnya berbagai dampak buruk yaitu ancaman proses
deindustrialisasi sektor kehutanan.
Pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar merupakan hak dan
kewajiban setiap warga negara. Pemerintah Indonesia memerlukan keterlibatan
semua pihak untuk menuntaskan seluruh aspek yang terkait dengan
permasalahan pembalakan liar, baik masyarakat, maupun pengusaha. Beban
pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar bukan hanya menjadi
permasalahan Pemerintah saja tetapi seluruh warga mempunyai kewajiban
untuk menjaga kelestarian hutan, selain itu juga warga negara mempunyai hak
untuk memiliki hutan yang lestari dan terjaganya keseimbangan ekosistem.
14
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
Pada saat ini, pembalakan liar tidak lagi hanya menjadi isu nasional.
Karena dalam perkembangannya, pembalaikan liar sudah berkembang menjadi
suatu tindak kejahatan yang terorganisir, melibatkan banyak pihak baik dalam
skala nasional maupun internasional, dan telah mencapai tingkat yang sangat
mengkhawatirkan. Bahkan berdasarkan hasil penelitian, dinyatakan bahwa
pembalakan liar berpotensi memberikan sumbangan yang besar bagi
pemanasan global. Oleh karenanya, dalam beberapa forum pertemuan the
Globe International on Climate Change and Global Warming di Berlin (3-4 Juni
2007), Brasilia (19-21 Februari 2008), dan di Tokyo (27-29 Juni 2008), \
pembalakan liar masuk dalam pembahasan. Disadari oleh banyak negara bahwa
untuk mengatasi masalah pembalakan liar ini diperlukan juga kerjasama antar
negara, baik dalam rangka pencegahannya maupun pemberantasannya.
C. Landasan Yuridis
Sebagai suatu tinjauan yuridis, sebagaimana disampaikan pada bagian
sebelumnya bahwa pengaturan dan dasar hukum dari pencegahan dan
pemberantasan pembalakan liar belum cukup komperehensif dan dapat menjawab
persoalan. Pada bagian ini, akan dikaji beberapa peraturan perundang-undangan
terkait dengan menganalisa kekurangan dan kelebihan dari amsing-masing
peraturan tersebut dalam rangka menunjang upaya pencegahan dan
pemberantasan pembalakan liar. Saat ini terdapat beberapa peraturan perundang
undangan yang dijadikan acuan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan
pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar. Namun dalam pelaksanaannya
peraturan perundang-undangan tersebut belum efektif karena terdapat beberapa
kelemahan. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain meliputi:
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada intinya
mengatur asas dan tujuan,, penguasaan hutan, status dan fungsi hutan,
15
, Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
pengurusan hutan, perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, Litbangdiklatluh
kehutanan, pengawasan, penyerahan kewenangan, masyarakat hukum adat,
peran serta masyarakat, gugatan perwakilan, penyelesaian sengketa kehutanan,
penyidikan, ketentuan pidana ganti rugi dan sanksi administratif, ketentuan
peralihan dan penutup. Undang-Undang Kehutanan ini tidak menyebut secara
langsung (secara eksplisit) tentang pembalakan liar. Undang-Undang Kehutanan
hanya mengatur norma yang bersifat perintah atau larangan dan disertai sanksi
baik sanksi administratif ataupun sanksi pidana. Sanksi administratif diancamkan
kepada pemegang izin di bidang kehutanan dan sanksi pidana diancamkan
kepada setiap orang yang melanggar norma lainnya, yang kesemuanya sangat
berkaitan erat dengan ketentuan-ketentuan teknis kehutanan. Walaupun
kejahatan di bidang kehutanan diawali dengan kegiatan penebangan hutan
tanpa izin, namun perkembangan lebih lanjut kasus tersebut telah berkembang
menjadi suatu tindak kejahatan yang terorganisir, melibatkan pihak-pihak tidak
saja dari dalam negeri tetapi juga mereka yang ada di luar negeri, dan bahkan
ada yang sudah berkembang ke arah timber money laundry yang melibatkan
beberapa negara. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
tidak mengatur tentang hal itu. Akibatnya banyak kasus pembalakan liar yang
bebas dari jerat hukum.
Kelemahan lain dari Undang-Undang tersebut antara lain, mengeriai
koordinasi antara aparat yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang kehutanan. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahlin
1999 tentang Kehutanan mengatur, bahwa "selain Pejabat Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingktJp
tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang
khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana". Dalam kasus pembalakan liar, kewenangan untuk
melakukan penyidikan terhadap pembalakan liar ini secara yuridis juga terdapat
pada institusi lain seperti Kejaksaan Negeri, Perwira TNI AL, dan aparat Bea
Cukai.
16
f:Jqskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pemba/akan liar-2008
Adanya beberapa institusi yang mempunyai kewenangan penyidikan dalam
kasus pembalakan liar ini menuntut koordinasi antar instansi. Dalam
perkembangannya, koordinasi antar institusi inilah sering menjadi permasalahan
dalam penyidikan kasus pembalakan liar. Yang terjadi penyidikan berjala11
sendiri-sendiri. Seringkali terjadi kesalahan interpretasi antara jaksa penul'!)tut '
umum dan penyidik terhadap pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam menghadapi kasus
pembalakan liar tertentu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan yang merupakan lex specialis tidak digunakan oleh
jaksa dan hakim.
Kelemahan lain yang terdapat dalam undang-undang ini adalah tid.ak
diaturnya mengenai sanksi terhadap pejabat yang turut serta membantu dalam
kegiatan pembalakan liar seperti dalam penerbitan perijinan dari produk
administrasi lain yang tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang
mengatur. Selain itu pula dalam Undang-Undang ini tidak diatur mengenai tindak
pidana yang dilakukan oleh perusahaan atau corporate crime sehingga sang,at
memberi peluang terhadap elit politik dan para pengusaha (korporasi) ya~g
bergerak di bidang pengelolaan hutan untuk memanfaatkannya guna
kepentingan dan keuntungan kelompoknya saja.
Hal lain yang berkaitan dengan pembalakan liar dan juga diatur dalam
Undang-Undang Kehutanan adalah masalah yang berkaitan dengan masyarakat
adat. Ketergantungan masyarakat adat akan hutan sangat besar, sehingga
karena desakan ekonomi dan maraknya pembalakan liar yang terjaai
memungkinkan mereka terlibat dalam kegiatan pembalakan liar. Di sisi lain,
mereka tidak mempunyai ketrampilan dan pengetahuan di luar kehidupan
mereka di hutan, karena selama ini mereka hidup, besar dan tinggal di dalam
dan di sekitar hutan. Akibatnya ketika hutan rusak, mereka yang pertama terkena
dampaknya. Undang-Undang Kehutanan, Pasal 67, mengakui keberadaan
masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dan
didasarkan pada penelitian para pakar. Apabila memang masih ada, Menteri
17
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008 '··1··.,
Kehutanan akan menetapkannya sebagai hutan adat. Namun apabila
kenyataannya masyarakat hukum adat sudah tidak ada lagi, maka tidak dapat
dihidupkan kembali. Dalam prakteknya pengakuan yang efektif tentang hak adat
sangat terbatas. Hanya sedikit mekanisme yang mengijinkan masyarakat adat
untuk memperoleh pengakuan sah atas tanah adat dan proses penamaan tanah
sangat rumit dan birokratis. Hingga saat ini peraturan pelaksana atas ketentuan
masyarakat adat berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan belum ada.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Lingkungan hidup sebagai suatu ekosistem terdiri atas sub sistem, yang
mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi dan geografi dengan corak ragam
yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup yang berlainan. Ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata,
baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber
daya alam tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan
pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan
beragam. Di pihak lain, daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya
tampung lingkungan hidup dapat menurun.
Dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak disebut secara
tegas mengenai pembalakan liar, yang disebutkan hanya mengenai kerusakan
lingkungan hidup (Pasal 14). Pembalakan liar secara tidak langsung
mengakibatkan kerusakan lingkungan. Pembalakan liar mengakibatkan hutan
gundul, tanah longsor, banjir, dan berkurangnya persediaan air bagi masyarakat
sekitar hutan. Dengan demikian, pembalakan liar dapat dikategorikan sebagai
tindak kejahatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan (ecocida). Namun
selama ini, jarang kasus pembalakan liar yang karena perbuatannya dikenakan
sanksi pidana perusakan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
18
,Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.
Berdasarkan Undang-Undang Agraria ditentukan bahwa Hak Atas Tanah
meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak
membuka tanah, hak memungut hasil hutan. Hak milik berdasarkan Undang
Undang Agraria adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah dan dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain.
Ketentuan tersebut memberikan pengertian bahwa pengaturan hak atas tanah
menurut Undang-Undang Agraria berbeda dengan pengaturan kawasan hutan
menurut Undang-Undang Kehutanan. Artinya Undang-Undang Kehutanan
mempunyai domain kawasan hutan, sedang Undang-Undang Agraria mempunyai
domain di luar kawasan hutan.
Undang Undang Agraria mengatur bahwa tanah dibagi ke dalam hak atas
tanah yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum bahkan dapat
dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan Undang-Undang Kehutanan mengatur
bahwa kawasan hutan tidak dibagi kedalam hak-hak atas tanah melainkan dibagi
kedalam fungsi hutan yang langsung dikuasai oleh Pemerintah dalam hal ini
Departemen Kehutanan. Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan
pemilikan tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur
dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan
hasil hutan. Menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan
hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan,
kawasan hutan dan hasil hutan serta mengatur perbuatan hukum mengenai
kehutanan.
Untuk menjembatani berlakunya Undang Undang Agraria dengan Undang
Undang Kehutanan telah ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Kehutanan,
Menteri Pertanian dan Kepala BPN Nomor 364/Kpts-11/1990, Nomor
519/Kpts/HK.050n/1990, Nomor 23-Vlll-1990 tentang Ketentuan-ketentuan
Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian HGU untuk Pengembangan Usaha
19
.Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan don Pemberantasan Pembalakan liar-2008
Pertanian. Berdasarkan keputusan bersama tersebut, mengenai kawasan hutan
dengan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), dapat dilepaskan
untuk budidaya pertanian, perkebunan termasuk pertambakan dan perikanan.
4. Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Pertambangan Umum.
Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 Undang Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan bahwa pada dasarnya Undang Undang Kehutanan
menampung kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan cara
pemberian ijin pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan dengan
ketentuan bahwa penggunaan kawasan hutan dilakukan tanpa mengubah fungsi
pokok kawasan hutan baik dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan
kawasan hutan lindung. Sedangkan pada kawasan hutan lindung dilarang
melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Adapun
pembangunan diluar kegiatan kehutanan tersebut antara lain pertambangan,
pembangunan jaringan listrik, telepon, instalasi air, kepentingan religi, serta
kepentingan pertahanan keamanan. Sedangkan pada sisi lain berdasarkan
Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 telah diatur ketentuan tentang
pertambangan umum, yang tentunya deposit tambang akan tersebar dimana saja
yang keberadaannya dapat d~ luar kawasan hutan maupun di dalam kawasan
hutan. Sepanjang deposit tambang tersebut berada di dalam kawasan hutan,
maka sesuai dengan ketentuan perundang-undang dibidang kehutanan dan yang
selama ini telah berjalan harus mendapat ijin pinjam pakai kawasan hutan dari
Menteri Kehutanan.
Pada prakteknya, kegiatan penambangan telah menimbulkan terjadinya
kerusakan hutan. Pembalakan liar juga terjadi di area pertambangan, namun
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tersebut tidak ada ketentuan yang
mengatur kewajiban penambang menjaga kawasan hutan areal tambangnya agar
tetap lesta ri.
20
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan don Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
5. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
Ada perbedaan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan hutan ketika
hutan merupakan sumber daya air bagi wilayah sekitarnya berdasarkan Undang
Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan berdasarkan Undang
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan Undang Undang
Kehutanan, hutan dikuasai oleh Negara, dan Negara memberi wewenang kepada
pemerintah untuk mengatur, mengurus, menetapkan baik dalam kaitannya dengan
hutan, kawasan hutan, hasil hutan maupun hubungan hukum antara orang dengan
hutan. Pengertian pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang
Undang Kehutanan adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab
dibidang kehutanan. Tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini menteri
meliputi pengaturan baik pengurusan hutan, pengelolaan hutan, pemanfaatan
hutan, pembinaan dan pengawasan dibidang kehutanan.
Disisi lain Undang Undang Sumber Daya Air memberikan pengertian air
adalah semua air yang terdapat pada, diatas ataupun dibawah permukaan tanah
termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yarig
berada di darat. Dengan pengertian air yang sangat luas berarti ketentuan
ketentuan Undang Undang Sumber Daya Air akan berlaku dan diberlakukan di
dalam kawasan hutan. Dengan demikian di dalam kawasan hutan akan ada dua
perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu Undang Undang Kehutanan yang
akan mengatur perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan sanksi
dibidang kehutanan, sedangkan disisi lain Undang Undang Sumber Daya Air akan
mengatur pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air,
hak guna usaha air, konservasi sumber daya air yang berada di dalam kawasan
hutan.
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah
mendesentralisasikan sejumlah kekuasaan hukum kepada pemerintah daerah.
21
.. .. Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pemba/akan liar-2008
Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberi kuasa untuk mengelola sumber
daya alam dalam yurisdiksi mereka dan bertanggung jawab untuk
mempertahankan kelestarian lingkungannya. Hal ini secara efektif berarti
pemerintah daerah memiliki sejumlah kekuasaan untuk mengelola sumber daya
alam dalam yurisdiksi mereka, selama mereka mengikuti peraturan perundang
undangan nasional yang ada. Pemerintah daerah juga diijinkan untuk memi!iki
bagian yang cukup substansial (80 %) dari pendapatan hasil hutan. Di sisi la1
in,
pemerintah pusat tetap mempunyai kekuasaan untuk mengembangkan kebijakfin
atas sejumlah masalah termasuk penggunaan dan konservasi hutan.
Dalam perkembangannya, ketentuan tersebut telah mengakibatkan
munculnya banyak peraturan daerah ataupun kebijakan daerah yang lebih
bertujuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dalam wilayahnya termasuk
hutan, demi meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kondisi ini diperparah
dengan adanya kewenangan bagi para bupati untuk menerbitkan ijin selama 1
tahun (Hak Pemungutan Hasil Hutan atau HPHH) untuk konsesi penebang~n
hutan berskala kecil (100 hektare) kepada masyarakat adat atau koperasi.
Kewenangan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999
tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan ProduksL
Ketentuan tersebut memuncullkan bentuk-bentuk pembalakan liar model baru.
Pada dasarnya tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999
adalah tujuan untuk memberikan hak bagi masyarakat setempat atas sumber daya
hutan yang ada. Namun dalam perkembangannya, kebijakan tersebut banyak
dimanipulasi. Kondisi ini mendorong dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Dalam revisi tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit
bahwa pemerintah daerah memiliki kuasa untuk mengelola hutan dan sumber
daya alam lainnya, kecuali sumber daya maritim.
Ketentuan baru ini menimbulkan perbedaan pandangan antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah mengenai kewenangan pengelolaan hutan yang
22
.. .Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan liar-2008
ada di daerah. Kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, masalah kehutanan
merupakan urusan bersama antar tingkatan pemerintahan (antara pemerintah
pusat, provinsi, dan kabupaten/kota). Bagi daerah sendiri, masalah kehutanan
merupakan urusan pilihan.
Pemerintah daerah memHiki kewenangan dalam pemberian izin pemanfaatan
kawasan hutan pada hutan lindung (pemungutan hasil hutan bukan kayu yang
tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam lampiran CITES dan pemanfaatan jasa
lingkungan), pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan
pada hutan produksi, dan pemberian izin pemungutan hasil hutan pada hutan
produksi.
Meski demikian, Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
menyatakan bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentang dengan Undang
Undang dan peraturan yang lebih tinggi. Gubernur diberi kuasa untuk menganulir
peraturan regional bila dianggap mengkontradiksi Undang-Undang dan peraturan
yang lebih tinggi. Sementara itu, daerah boleh mengajukan keberatan kepada
Mahkamah Agung bila mereka tidak setuju dengan keputusan Gubernur
membantu pemerintah pusat untuk menganulir peraturan daerah.
7. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang. Penataan Ruang
Masalah pembalakan liar terkait juga dengan Undang Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam Undang-Undang tersebut
dinyatakan bahwa ruang dapat dibedakan menjadi fungsi lindung dan fungsi
budidaya. Sedangkan fungsi lindung dapat berupa hutan lindung, kawasan suaka
alam, atau kawasan pelestarian alam dan fungsi budidaya antara lain dapat
berupa hutan produksi. Pengaturan tata ruang ini sangat terkait dengan
pengaturan fungsi hutan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan. Paling tidak dalam penyusunan rencana tata
ruang dan tata wilayah, terkait dengan penetapan hutan, perlu diperhitungkan
23
.. Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan don Pemberantasan Pemba/akan Liar-2008
sebagai bagian upaya pencegahan pembalakan liar. Karena pembalakan liar
selama ini tidak hanya terjadi di kawasan budidaya (seperti di hutan produksi)
tetapi juga terjadi di kawasan lindung (seperti di hutan suaka alam, hutan lindung,
dan lain-lain).
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP).
Dalam putusan pengadilan, hakim lebih menggunakan ketentuan dalam
KUHP yang sanksi pidana maupun dendanya relatif lebih ringan karena menurut
pendapat hakim tindakan pelaku pembalakan liar sesuai dengan kategori dalam
KUHP. Pemberian sanksi yang ringan tersebut tidak membuat jera para pelaku
pembalakan liar, terutama para cukong pemilik modal yang jarang tersentuh oleh
hukum. Penjatuhan vonis hukum terhadap pelaku pembalakan liar terlalu ringan
dan tidak sepadan dengan bobot kejahatannya. Hal ini sering dijadikan dasar
acuan para pelaku kejahatan pembalakan liar untuk lebih berani lagi dalam
melakukan perbuatan pembalakan liar.
Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengkualifikasikan pelaku tidak
pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut
serta melakukan perbuatan pidana dapat diterapkan dalam kejahatan pembalakan
liar yang melibatkan banyak pihak. Namun demikian beban pidana yang harus
ditanggung secara bersama dalam hal terjadinya pembalakan liar juga dapat
mengurangi rasa keadilan masyarakat, karena dengan kualitas dan akibat yang
tidak sama terhadap pelaku turut serta, dapat dipidana maksimum sama dengan si
pembuat menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP, sedangkan ternyata peranan
pelaku utamanya sulit untuk ditentukan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
Sumber daya alam yang antara lain berupa hutan produksi, hutan lindung,
kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, hasil hutan dan
24
, Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan don Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
satwa yang harus dilestarikan dan didayagunakan dengan penuh rasa tanggung
jawab, karena mempunyai fungsi produksi, fungsi lindung antara lain pengaturan
tata air, pencegahan banjir dan erosi, memelihara kesuburan tanah, kelestarian
lingkungan hidup, dan fungsi konservasi keanekaragaman hayati yang merupakan
penyangga kehidupan.
Kelemahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tersebut tidak
menyebutkan secara spesifik mengenai pembalakan liar namun hanya
menyebutkan mengenai kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan
manusia, dan tidak menyebutkan secara jelas tindakan-tindakan yang terma~uk
pembalakan liar serta belum menjamin terselenggaranya perlindungan hutan
secara menyeluruh.
1 O.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusun1an '
Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawas:an
Hutan
Kelemahan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 adalah belum
implementatif. Kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang tidak
berorientasi pada kelestarian hutan mengakibatkan banyak terjadinya pengalihan
fungsi hutan alam baik untuk perkebunan, pemukiman, maupun kegiatan
pembangunan yang lainnya. Pada akhirnya status kayu hutan sebagai milik
negara berpengaruh pada sikap dan tindakan masyarakat. Karena sistem
pengelolaan tidak menjamin kejelasan hak (property right) atas kayu sebagai milik I
negara maka hilangnya kayu dari hutan tidak menyebabkan kerugian finansial bagi
siapapun. Pada akhirnya masyarakat baik secara individu maupun korpor~si
(pengusaha) banyak melakukan penebangan kayu tanpa ijin untuk diperjualbelikan
maupun untuk keperluan industrinya.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 ini sudah direvisi menj<adi
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemantaatan Hutan. Namun Peraturan
25
... N~skah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
Pemerintah ini juga belum implementatif. Meskipun dalam PP ini terdapat hal baru
yang diatur, yang sangat bermanfaat guna mencegah terjadinya pembalakan liar,
yaitu mengenai pemberdayaan masyarakat setempat. Masyarakat setempat disini
adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan I atau sekitar hutan yang merupakan
kesatuan komunitas sosial berdasarkan mata pencaharian yang bergantung pada
hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib
kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan. Masyarakat adat juga termasuk
dalam masyarakat setempat, yang ikut diberdayakan dalam rangka pencegahan
pembalakan liar.
11. lnstruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan
Kayu secara ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh Wilayah
Republik Indonesia.
lnpres ini menginstruksikan kepada instansi terkait untuk melakukan
percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan
peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Menindak tegas dan
memberikan sanksi terhadap oknum petugas di lingkungan instansinya yang
terlibat dengan kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan
dan peredarannya. Menginstruksikan untuk melakukan kerjasama dan saling
berkoordinasi untuk melaksanakan penebangan kayu secara ilegal di dalam
kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Selanjutnya dengan memanfaatkan informasi dari masyarakat yang berkaitan
dengan adanya kegiatan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya.
lnpres ini mengarahkan pemimpin dari 18 badan pemerintah untuk
bekerjasama dan berkoordinasi untuk menghapuskan pembalakan liar di
Indonesia; dan menyediakan instruksi spesifik untuk 10 dari para pemimpin ini
dalam sekumpulan cara yang harus mereka lakukan untuk mencapai tujuan ini,
antara lain:
26
, , Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
a. Mengarahkan Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan untuk
mengkoordinasi dan mempercepat penghapusan pembalakan liar; dan untuk
melaporkan pada Presiden kemajuan inisiatif ini setiap 3 bulan;
· b: Menghimbau Menteri Kehutanan untuk mengajukan usaha - usaha
pencehajan yang dapat diambil untuk mengatasi pembalakan liar pada kantor
Jaksa Agung;
c. Menghimbau Jaksa Agung untuk menuntut para pelaku kejahatan kehutanan
dengan menggunakan Undang-Undang secara maksimal;
d. Menghimbau Jaksa Agung untuk mempercepat penyelidikan dan proses -
proses yudisial untuk menuntut para pelaku kejahatan kehutanan;
e. Menghimbau Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan Bupati untuk mencabut
dan merevisi peraturan - peraturan regional yang berkontradiksi dengan
Undang-Undang nasional;
f. Menghimbau Gubernur dan Bupati untuk mencabut ijin - ijin usaha untuk
industri pengolah kayu yang menggunakan kayu ilegal; dan
g. Memanggil para Gubernur dan Bupati untuk mencabut ijin usaha industri
pengolah kayu yang beroperasi dengan mengkontradiksi Undang-Undang
nasional.
Untuk melakukan penanganan sesegera mungkin terhadap barang bukti
hasil operasi pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan
dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan atau alat-alat bukti
lain yang digunakan dalam kejahatan dan atau alat angkutnya untuk penyelamatan
nilai ekonomisnya. Menginstruksikan kepada menteri keuangan untuk
mengalokasikan biaya memberantas pembalakan liar melalui APBN pada masing
masing instansi untuk kegiatan operasional maupun insentif bagi pihak yang
berjasa. Kepada Gubernur dan Bupati/Walikota diinstruksikan untuk
mengalokasikan biaya memberantas pembalakan liar melalui APBD masing
masing. Menginstrusikan kepada Gubernur, Bupati, Walikota untuk mencabut izin
usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan kayu yang telah
27
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
dikeluarkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
lnpres tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif, salah satu
kendalanya adalah masalah pendanaan yang belum terealisir. Selain itu pula
kelemahan lainnya adalah sulitnya melakukan koordinasi antar instansi terkait
dalam memberantas pembalakan liar, menjaga konsistensi sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing, bukan koordinasi dalam upaya pemberantasan
pembalakan liar. Hal lain adalah sinergisitas antara upaya-upaya yang dilakukan
oleh masyarakat, kepolisian, kejaksaan dengan putusan pengadilan.
Dari sudut ilmu perundang-perundangan, lnpres sebagai salah bentuk
instrumen hukum juga memiliki kelemahan, dimana lnpres tidak termasuk dalam
hirarkhi peraturan perundang-undangan dan tidak dapat memuat sanksi baik
pidana maupun administratif sehingga lnpres ini tidak mempunyai daya paksa dan
daya guna yang lebih kuat. lnpres ini lebih bersifat arahan dan instruksi dari
pimpinan kepada bawahan.
28
., .Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan liar-2008
BAB Ill
KERANGKA KONSEPTUAL
A. Teori Pembentukan Hukum
Dalam pembentukan dan penyusunan Undang-Undang tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Pembalakan Liar, ada beberapa persyaratan untuk
melahirkan suatu undang-undang yang efektif sebagaimana dikemukakan oleh
William M. Evans. Evans berpendapat ada 7 (tujuh) syarat agar hukum atau
undang-undang yang dihasilka bisa berlaku efektif11.
Pertama, hukum harus dirumuskan dalam suatu bentuk peraturan
perundang-undangan yang memiliki derajat yang lebih tinggi, misalnya dalam
bentuk undang-undang. Kedua, hukum yang dirumuskan betul-betul didasarkan
sumber yang kuat, termasuk argumentasi yang berkaitan dengan dukungan dan
legitimacy secara sosial di masyarakat. Ketiga, peraturan yang dirumuskan itu,
jelas tujuan da rumusannya. Jadi masyarakat mengerti apa tujuan dari undang
undang tersebut dan aturan yang dirumuskan dengan jelas.
Keempat, memberikan waktu dan kesempatan untuk menyesuaikan keiatan
melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan yang akan diterapkan, artinya
masyarakat diberi waktu untuk memahami maksud dari isi peraturan perundang
undangan tersebut. Kelima, komitmen dari aparat penegak hukum untuk
memberikan contoh dan teladan sesuai dengan ketentuan peraturan yang baru
dan komitmen melaksanakan tugas penegakan hukum secara konsisten.
Keenam, sanksi dan insentif. Artinya tingkat ketaatan terhadap hukum
secara negatif dapat disebabkan oleh sanksi yang dirumuskan dalam peraturan
tersebut, dan sebaliknya secara positif, tingkat ketaatan ini muncul karena
adanya insentif yang diperoieh dari pelaksanaan suatu peraturan peundang-
11 William Evans dalam Lawrence M Friedman, Law and Society (Prentile-Hall,lnc, Engleewood,Cliffs, New Jersey,07632,tanpa tahun} hal 64-65
29
, Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
undangan. Ketujuh, perlindungan maksimal bagi korban atas pelanggaran
terhadap peraturan yang dirumuskan tersebut. Dengan demikian mengacu pada
pendapat evans tersebut, dalam penyusunan Undang-Undang tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar harus memperhatikan 7
(tujuh) syarat agar undang-undang ini yang dihasilkan bisa berlaku efektif.
Selanjutnya dalam mengembangkan sistem hukum dalam upaya
penanganan pembalakan liar tersebut mengacu pada pendapat Friedman
terdapat 3 (tiga) elemen sistem hukum yakni : substansi (substance), struktur
(Structure), dan budaya hukum (legal cu/ture)12. Terkait dengan supstansi, dalam
pembentukan hukum tentang illegal logging harus memperhatikan berbagai
aspek pendekatan hukum yang mencakup berbagai bidang hukum, baik pidana,
perdata, korporasi dan perkembangan hukum internasional yang terkait dengan
masalah pembalakan liar. Terkait dengan struktur, dalam penanganan
pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar harus dibangun suatu otoritas
atau lembaga yang kuat yang bertanggung jawab dalam menangani masalah ini,
dimana lembaga tersebut harus bebas dari pengaruh dan intervensi kekuatan
mana pun, termasuk kekuatan politik. Terkait dengan budaya hukum, yang
mencakup kesadaran dan komitmen bersama, terutama para penegak hukum,
penyelenggara pemerintahan (pejabat negara) dan Negara, yakni mengenai
penting dan strategisnya upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan
liar.
B. Pengertian Pembalakan Liar (Illegal Logging)
Konstruksi baku mengenai pengertian dan definisi illegal Jogging sampai
saat ini belum terjadi kesepakatan. Beberapa kalangan mendefinisikan illegal
Jogging berdasarkan sudut pandang masing-masing. Secara etimologi, illegal
logging berasal dari kata "il/egaf' yang berarti praktek tidak sah dan "logging"
yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu. Dengan demikian illegal Jogging
dapat diterjemahkan sebaga~ praktek pemanenan kayu secara tidak sah. Dari
12 Lawrence M. Friedman, American Law, (New York & London: W.W. Norton & Company, 1984), hal.5. 30
. N<;1skah Akademik RUU tentang Pencegahan don Pemberantasan Pemba/akan Liar-2008
aspek simplikasi semantik diartikan sebag.ai praktek penebangan liar, sedangkan
dari aspek integratif diartikan sebagai praktek pemanenan kayu beserta proses
prosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang
telah ditetapkan. 13
Dengan mengacu pada terminologi bahasanya, Riza Suarga 14
mendefinisikan illegal logging sebagai suatu praktik eksploitasi hasil hutan
berupa kayu dari kawasan hutan Negara melalui aktifitas penebangan pohon
atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil
tebangan secara tidak sah. Kegiatan illegal logging ini meliputi kegiatan illegal
processing dan illegal trade.
Illegal processing merupakan semua kegiatan proses lanjutan terhadap
kayu hasil tebangan secara illegal. Ruang lingkup illegal processing adalah: 1)
hak kepemilikan, menguasai atau memiliki atau meyimpan kayu hasil tebangan
secara ilegal; 2) pergerakan kayu, meliputi mengangku atau mengeluarkan kayu
darikawasan hutan negara hasil tebangan secara ilegal, dan 3) pengolahan
kayu, merupakan kegiatan pengolahan kayu dari bahan baku logs hasil tebangan
secara illegal. Sedangkan illegal trade merupakan proses lebih lanjut yang dapat
memicu atau menjadi alasan kegiatan eksploitasi secara illegal tetap berjalan.
Ruang lingkup illegal trade meliputi: 1) perdagangan; 2) penyelundupan; 3)
perizinan; dan 4) pelanggaran.
Praktek illegal logging, dengan mengacu pada pendapat Prasetyo15
memiliki 7 dimensi, yaitu (1) perizinan (apabila kegiatan tersebut tidak ada
izinnya, atau belum ada izinnya, atau izinnya yang telah kadaluarsa); (2) praktek
(apabila pada prakteknya tidak menerapkan praktek logging yang sesuai
peraturan); (3) lokasi (apabila dilakukan di lokasi di luar izin, menebang di
kawasan konservasi atau hutan lindung, atau asal usu I lokasi tidak dapat
13 Riza Suarga, Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global, Banten: Wana Aksara, 2005, hal.9
14 Riza Suarga, Ibid, hal 6-7 15 Prasetyo, D. 2003. Illegal Logging, Suatu Malpraktek Bidang Kehutanan, makalah pada Semiloka lnisiatif Daerah dalam Penanggulangan Illegal Logging, 9 Januari 2003, APHI, Samarinda, halaman 1.
31
.,Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pemba/akan Liar-2008
ditunjukkan); (4) produksi kayu (apabila kayunya sembarang jenis atau
dilindungi, tidak adaa batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada
tanda pengenal perusahaan); (5) dokuman (apabila tidak ada dokumen sahnya
kayu); (6) pelaku (apabila orang perorangan atau badan usaha tidak memegang
izin . usaha logging atau melakukan kegiatan pelanggaran hukum di bidang
kehutanan), dan (7) penjualan (apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen
maupun ciri fisik atau kayu diselundupkan).
Setiap dimensi muncul akibat berbagai macam sebab yang saling terkait
satu sama lain. Masih menurut Prasetyo16, praktek illegal logging disebabkan
oleh 6 faktor, yaitu (1) krisis ekonomi; (2) perubahan tatanan politik; (3) lemahnya
koordinasi antara aparat penegakan hukum; (4) adanya kolusi, korupsi, dan
nepotisme; (5) lemahnya sistem pengamanan hutan dan pengamanan hasil
hutan, serta (6) harga kayu hasil tebangan liar yang lebih murah.
Sedangkan menu rut Nana Suparna 17 illegal logging timbul karena: (1)
sistem pengelolaan hutan yang salah; (2) tingkat kesejahteraan pejabat, petugas
dan masyarakat sekitar hutan yang rendah; (3) mentalitas yang tidak baik; dan
(4) kontrol yang lemah, baik kontrol instansional maupun kontrol sosial. Lain
halnya dengan pendapat Laode M Kamaluddin18. Menurut Kamaludin, praktek
illegal logging disebabkan oleh 5 hal yaitu (1) over demand kayu di dalam negeri;
(2) selisih harga ekspor kayu di luar negeri; (3) pertumbuhan penduduk; (4)
dorongan meningkatkan pendapatan riil sebanyak-banyaknya; dan (5) desakan
16 Ibid. Halaman 1 O 17 Nana Suparna, 2005, Illegal Logging Dari Sisi Sistem Pengelolaan Hutan, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional mengenai Illegal Logging, Permasalahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia Didekati dari aspek Hukum, Ekonomi, dan Manajemen, diselenggarakan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta, 16 mei 2005 di Gedung Wanabakti-Jakarta, halaman 1.
18 Kamaludin, Laode M., 2005. Kerugian Negara yang Ditimbulkan Akibat Illegal Logging dan Antisipasi Ditinjau dari Aspek Ekonomi dan Ekologi, Makalah disampaikan pada acara Seminar Nasional "Illegal Logging, Permasalahan dan Penanggulangannya di Indonesia, Tinjauan Hukum, Ekonomi, dan Manajemen, diselenggarakan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 16 Mei 2005 di Gedung Manggala Wanabakti- Jakarta, halaman 1.
32
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
ketersediaan pangan (termasuk peladang berpindah-pindah).Kelima variabel ini
harus dikelola untuk mengatasi masalah illegal logging di Indonesia.
Namun yang pasti, praktek illegal logging menimbulkan kerugian negara
secara ekonomis, ekologis, dan politis. Secara ekonomis, karena pungutan
provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan pajak ekspor yang tidak dibayar.
Secara ekologis, karena illegal logging mengakibatkan punahnya flora fauna
yang ada di dalam hutan, ekosistem rusak, hutan menjadi gundul
(deforestation), kawasan resapan berkurang, erosi tanah (soil erotion),
pemanasan bumi, bencana banjir dan tanah longsor. Dan secara politis, karena
Indonesia terikat dengan beberapa komitment global untuk menjaga kelestarian
hutan, praktek illegal logging yang masih berlangsung hingga saat ini menjadikan
posisi lndonesi kurang menguntungkan di mata dunia.
Hasil Temu Karya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendefinisikan
illegal logging sebagai penebangan liar sekaligus merusak hutan. Dari pengertian
ini timbul istilah baru yaitu penebangan liar yang artinya penebangan tanpa izin
dan/atau dengan izin tetapi melanggar ketentuan dalam perizinan, contoh
menebang melewati batas yang ditentukan19•
Definisi lain menyebut bahwa illegal logging sebagai rangkaian kegiatan
yang mencakup penebangan, pengangkutan, penjualan, proses produksi,
penjualan hasil produksi baik di dalam maupun ke luar negeri (penyelundupan)
dan semua kegiatan tersebut tidak sah atau tanpa izin, bertentangan dengan
peraturan yang berlaku. Dari pengertian tersebut, unsur-unsur perbuatan illegal
logging adalah penebangan, pengangkutan, penjualan, proses produksi,
penyelundupan yang mengakibatkan kerusakan hutan dan kerugian negara
secara melawan hukum20•
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tidak
memberikan definisi secara tegas apa yang dimaksud dengan praktek
19 Ngurah Gede, "Apakah Perlu RUU Khusus untuk Memberantas Illegal logging: Suatu Kajian," hal. 2. 20 Sukardi, Illegal logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua}, Yogyakarta: Universitas
Atma Jaya Yogyakarta, 2005, hal. 73. 33
. ,.f':/a~kah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
pembalakan liar atau penebangan kayu secara liar/ tidak sah/tanpa hak, namun
undang-undang tersebut melarang perbuatan sebagai berikut:
1. menebang di luar blok yang sudah ditentukan;
2. menebang pohon dengan menyalahi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
(SKSHH); dan/atau
3. menebang dengan meiebihi volume dan luas lahan tebangan melebihi
toleransi yang sudah ditentukan, yaitu sebesar 5% (lima persen).
Terkait dengan penggunaan istilah illegal logging, hasil temuan lapangan
menunjukan penggunaan istilah illegal logging hanya dikenal oleh kalangan
pengusaha yang bergerak di sektor kehutanan dan masyarakat golongan
tertentu yang memiliki tingkat pendidikan atau wawasan yang luas, sedangkan
untuk masyarakat awam, istilah tersebut kurang dipahami. Masyarakat awam di
sekitar hutan lebih mengenal istilah penebangan hutan atau pembalakan secara
liar, lebih khusus lagi istilah yang lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh
masyarakat luas adalah pencurian kayu di dalam hutan.
Prinsip pemberlakuan suatu undang-undang adalah berlaku umum,
dengan demikian penerapan suatu undang-undang ditujukan untuk seluruh
lapisan masyarakat, tidak dikhususkan untuk golongan tertentu. Oleh karena itu
penggunaan istilah dalam undang-undang sudah seharusnya menggunakan
istilah yang dapat dimengerti oleh seluruh golongan masyarakat.
Dari beberapa pengertian illegal logging yang telah disebutkan, maka
pengertian pembalakan liar yang digunakan dalam naskah akademis ini adalah
kegiatan penebangan pohon di dalam hutan yang dilakukan dengan tidak
memenuhi ketentuan yang berlaku yang antara lain meliputi keabsahan tempat
asal kayu, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, administrasi dan
dokumen angkutan, mutasi, transaksi, penjualan, atau pemindahtanganannya21•
21 Lihat pengertian kayu legal dalam MOU between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Great Britain and Nothem Irland on Coorperation to Improve Forest Law Enforcement
34
,,Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
Praktek pembalakan liar yang selama ini terjadi menggunakan modus
operandi yang berbeda-beda. Secara umum modus operandi yang sering
digunakan oleh pelaku illegal logging dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
berdasarkan pelaku kegiatan (subyek) dan kegiatan yang dilakukan (obyek).
a) Berdasarkan subyeknya
Modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku illegal logging yaitu
sebagai berikut:
(1) perorangan
a. menebang tanpa hak;
b. membakar hutan;
c. memiliki, mengangkut, membeli, menjual kayu tanpa dilengkapi
dokumen.
(2) korporasi
a. menebang tanpa hak;
b. merambah, mengangkut, dan/atau menadah kayu secara ilegal;
c. menyalahgunakan izin.
(3) perusahaan berbadan hukum/swasta
a. menebang tidak sesuai prosedur;
b. merambah, bakar hutan;
c. memanipulasi dokumen/SKSHH;
d. menyalahgunakan izin;
e. membeli, menerima, menyimpan, menadah kayu hasil curian;
f. menjual kayu hasil curian.
and Governance and to Combat Illegal Logging and the International Trade in 11/egaly, tanggal 18 April 2002, dalam Rahmi Hidayati et. al., Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan, Banten: Wana Aksara, 2006.
35
.. Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan don Pemberantasan Pembalakan liar-2008
(4) BUMN/BUMD
a. menguasai lahan yang bukan haknya;
b. menyalahgunakan dokumen;
c. memanipulasi data (dokumen);
d. tidak membayar IHH dan PSDH;
e. membeli menampung kayu hasil curian;
f. menyeludupkan kayu ilegal ke luar negeri.
b) Berdasarkan obyeknya
Modus operandi yang digunakan oleh pelaku pada umumnya berupa
kegiatan sebagai berikut:
(1) di kawasan hulu (asal) kayu
a. kayu berkedok untuk keperluan sosial seperti pembangunan Aceh pasca
tsunami, dan lain-lain penebangan dilakukan tanpa izin dari pejabat yang
berwenang (liar);
b. penebangan dengan dilengkapi izin tetapi dilakukannya di luar blok areal
Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman lndustri (HTI), atau lzin
Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dimilikinya, atau di luar area RKT;
c. pemerintah daerah masih memberikan izin yang sebenarnya sudah di luar
batas kewenangannya;
d. penebangan liar dengan melibatkan masyarakat setempat tetapi
digerakkan atau didanai oleh cukong;
e. melibatkan oknum pejabat pemerintah/aparat sebagai backing atau sebagai
koordinator kegiatan penebangan liar;
f. memanipulasi kelompok masyarakat untuk turut serta melakukan
pembalakan liar;
36
•. Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan liar-2008
g. pelaku bekerja sama dengan pengusaha lokal untuk membuka lahan
perkebunan, dimana setelah mendapat IPK fisik kayu yang berada diatas
areal sesuai dengan izin tersebut diambil kayunya/tebang sementara
kegiatan perkebunan tidak dilakukan;
h. pembukaan wilayah-wilayah yang terisolir dengan alasan pembangunan
melalui pembangunan fasilitas umum seperti jalan, rumah ibadat dan lain
lain;
(2) di kawasan hilir (tujuan kayu/pelabuhan)
a. kayu tidak dilengkapi dengan dokuman SKSHH;
b. kayu dilengkapi dengan dokumen palsu: blanko dan isinya palsu; atau
blanko asli isinya palsu; atau SKSHH diterbitkan dari daerah lain bukan
dari daerah asal kayu.
c. muatan kayu secara fisik di kapal/truk tidak sesuai dengan yang tertera
dalam dokumen SKSHH;
d. SKSHH digunakan berulang-ulang (dicabut dari pos kehutanan atau
lembar ke-1 dan ke-2 dokumen SKSHH tidak diisi masa berlakunya dan
identitas alat angkutnya);
e. memanfaatkan risalah lelang;
f. kayu diseludupkan dengan dokumen palsu atau tanpa dokumen.
Pada dasarnya setiap kegiatan pemanfaatan hutan dan hasil hutan harus
dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan
pelaksanan yang berlaku. Dalam hal ini untuk dapat disebut sebagai kayu legal
maka kayu tersebut harus memiliki keabsahan tempat asal kayu, izin
penebangan, sistem dan prosedur penebangan yang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, kelengkapan administrasi dan dokumen angkutan, mutasi,
transaksi, penjualan, atau pemindahtanganannya.
37
. _Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
C. Pembalakan Liar sebagai Tindak Pidana
Praktek pembuatan peraturan perundang-undangan pidana menunjukkan
adanya suatu gejala baru, ·yaitu penggunaan hukum pidana sebagai instrumen
kebijakan pemerintah22• Dalam bidang ekonomi, kesehatan, perlindungan
lingkungan dan lalu lintas, sulit kita mengkualifikasikan hukum pidana secara lain
daripada sebagai suatu hukum yang mengatur dan mengendalikan mekanisme
politik pemerintah.
Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum)
pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.
Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan "diandalkan" sebagai
salah satu sarana politik kriminal. Bahkan akhir-akhir ini, pada bagian akhir
kebanyakan produk perundang-undangan hampir selalu dicantumkan sub-sub
tentang "ketentuan pidana"23.
Ketentuan pidana itu sendiri merupakan bagian dari perundang-undangan
yang pembentukannya merupakan kekuasaan/kewenangan lembaga legislatif
termasuk didalamnya menetapkan apa yang dilarang dan sanksi apa yang
dirumuskan/ditetapkan apabila perbuatan tersebut dilanggar.
Kebijakan legislasi hampir selalu menggunakan hukum pidana untuk
menakut-nakuti pelaku tindak kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang.
Fenomena semacam ini memberi kesan seolah-olah dirasakan kurang sempurna
atau hambar bila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan
pidananya24.
Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah yang
sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tidak
terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya,
22 Roeslan Saleh, Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Makalah Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum Ull, 15 Juli 1993, hal. 5.
23 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hal. 39.
24 Ibid., him. 40. 38
; · Nf1skah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pemba/akan Liar-2008
masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi dipahami
secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi
perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi 25.
lmplikasi dari perkembangan pembalakan liar dalam bentuk modus
operandi maupun pelaku, bukan hanya penegakan hukum dalam upaya preventif
saja yang tidak dapat berjalan dengan baik, akan tetapi upaya represif dalam
bentuk penegakan hukum pidana juga tidak lagi efektif. Ketentuan pidana
kehutanan sebagai lex specialis (kekhususan/pengecualian) dari peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan penebangan pohon di dalam hutan
secara tidak sah yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1990 dan PP Nomor 28 tahun 1985, maupun peraturan
perundang-undangan sebagai lex genera/is (umum) yaitu Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang
Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) maupun ketentuan pidana lainnya yang terkait, tidak dapat
mengakomodasi perkembangan kejahatan pembalakan liar (illegal logging),
sehingga diperlukan politik hukum pidana untuk memenuhi kebutuhan
perkembangan kejahatan tersebut 26.
Dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka kebijakan hukum pidana
(politik hukum pidana) merupakan bagian dari kebijakan kriminal/politik kriminal
(criminal policy), disamping kebijakan yang tidak menggunakan hukum pidana
(nonpenal policy).
Ditinjau dari sudut politik hukum, kebijakan penal berarti mengadakan
pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik
dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna27. Di samping itu, kebijakan
penal dapat pula berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan
25 M. Shofehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana - Ide Dasar Double Track System Dan lmplementasinya, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 5.
26 Sukardi, Op. Cit haf. 27 27 M. Sholehuddin, Op. Cit., hal. 161.
39
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk
masa yang akan datang28.
Menurut Prof. Sudarto, pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang
bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang
berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan
dalam pemberian sanksi tersebut29.
Dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka
"pemidanaan" yang biasa juga diartikan "pemberian pidana" tidak lain merupakan
suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu
untuk benar-benar dapat terwujud, direncanakan melalui beberapa tahap yaitu :
tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang; tahap pemberian pidana
oleh badan yang berwenang, dan tahap pelaksanaan pidana oleh instansi
pelaksana yang berwenang 30.
Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian tindak pidana
yaitu : (1) ada suatu perbuatan, (2) perbuatan itu dapat dikenakan hukuman, dan
(3) perbuatan itu melanggar Undang-Undang tindak pidana. Pengertian ini
konsisten dengan asas legalitas (nul/um de/ictum) seperti yang ditegaskan dalam
Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang1 Hukum Pidana bahwa "tiada suatu
perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan pidana dalam undang
undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu".
Sampai saat ini proses hukum terhadap kasus-kasus Pembalakan liar
masih mengacu pada ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal
50 jo Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1990, dan PP Nomor 28 Tahun 1985 sebagai lex specialis. Selain itu,
terdapat beberapa peraturan perundangan-undangan lainnya yang terkait yang
merupakan lex genera/is dari kejahatan di bidang kehutanan yaitu KUHP dan
28 M. Sholehuddin, Ibid., hal. 93 dan hal. 109. 29 Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1992, hal. 89. 30 Ibid, hal. 91.
40
. .Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002. Dari peraturan perundang-undangan
tersebut, baik yang bersifat lex specialis maupun yang bersifat lex genera/is
belum mengatur secara rinci mengenai Pembalakan liar sebagai salah satu
kejahatan di bidang kehutanan.
Pada kenyataannya, pembalakan liar semakin berkembang dan semakin
rumit untuk diberantas sehingga perlu dikaji dari aspek hukum pidana sebagai
lex specialis dari kejahatan di bidang kehutanan. Dari kajian beberapa penulis
mengenai Pembalakan Hardan hasil penelitian di lapangan terdapat fakta bahwa:
1. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kehutanan
atau pembalakan liar mengakibatkan terjadinya perbedaan dasar hukum
yang digunakan aparat untuk penanganan pembalakan liar berdasarkan
kepentingan tertentu.
Selain itu, faktor ketidakjelasan arti kata dalam peraturan perundang
undangan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda antara pihak yang
berwenang, antara lain terdapat perbedaan persepsi atau batasan yang
mencakup pengertian pembalakan liar antar instansi yang terkait dengan
penanganan pembalakan liar.
2. Pembalakan liar telah meluas tidak hanya terjadi di hutan produksi tetapi
sudah merambah ke kawasan hutan lindung (kawasan konservasi). Kondisi
tersebut telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi
kelangsungan hidup bangsa dan negara karena rusaknya sumber daya alam
yang menjadi penyangga kehidupan manusia.
3. Pembalakan liar semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya.
Peran masyarakat, pemodal dan pedagang yang bekerjasama dengan
oknum pejabat/aparat pemerintah dan aparat penegak hukum telah
menghancurkan tatanan pengelolaan hutan dan peredaran atau perdagangan
kayu dan produk kayu.
4. Pembalakan liar sudah semakin meluas dan kompleks serta sudah
merupakan kejahatan yang terorganisasi (organized crime) yang didanai atau
41
,Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pemba/akan Liar-2008 ..
dibiayai oleh orang tertentu atau orang-orang yang berpengaruh sehingga
sulit diberantas.
Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana
tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam
pemidanaan. Dengan kata lain, perumusan tujuan pernidanaan diarahkan
untuk dapat rnernbedakan sekaligus rnengukur sejauh rnana jenis sanksi,
baik yang berupa "pidana" rnaupun "tindakan" yang telah ditetapkan pada
tahap kebijakan legislasi itu dapat rnencapai tujuan secara efektif.
Meskipun jenis sanksi untuk setiap bentuk kejahatan berbeda-beda,
narnun yang jelas, sernua penetapan sanksi dalam hukurn pidana harus tetap
berorientasi pada tujuan pernidanaan itu sendiri. Tujuan dari kebijakan
rnenetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik
krirninil dalarn arti keseluruhannya yaitu "perlindungan rnasyarakat untuk
rnencapai kesejahteraan". 31
Berkaitan dengan tujuan politik krirninil, Rancangan KUHP
rnerurnuskan tujuan pernidanaan yang bertolak dari pernikiran bahwa sistern
hukurn pidana rnerupakan satu kesatuan sistern yang bertujuan (purposive
system atau teleological system) dan pidana hanya rnerupakan alat/sarana
untuk rnencapai tujuan, rnaka Rancangan Undang-Undang tentang KUHP
rnerurnuskan tujuan pernidanaan yang bertolak pada keseirnbangan dua
sasaran pokok, yaitu "perlindungan rnasyarakat" (general prevention) dan
"perlindungan/pernbinaan individu" (special prevention). 32
Sedangkan pidana rnengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai
berikut: 33
31 Ibid., hal. 91. 32 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia,
Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor .. .. Tahun ... tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tahun 2004, hal. 8.
33 Ibid, hal. 4. 42
,. Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan don Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
1) pidana itu pad a hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan
atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang
mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3) pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak
pidana menurut undang-undang.
Kebijakan menetapkan jenis sanksi pidana apa yang dianggap paling
baik untuk mencapai tujuan, setidak-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat
dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif. Masalah pemilihan
berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling
baik, paling tepat, paling patut, paling berhasil atau efektif, jelas merupakan
masalah yang tidak mudah. Dalam hal ini Fitzgerald berpendapat bahwa "the
problem of selecting the appropriate sentence is not one which can be solved
by normal legal techniques. In fact, it is not the typical sort of legal problem" 34
Berkaitan dengan penetapan sanksi pidana untuk mencapai tujuan
tersebut, menurut H.L. Packer, pembenaran atas "punishmenf' didasarkan
pada satu atau dua tujuan sebagai berikut 35:
1) untuk mencegah terjadinya. kejahatan atau perbuatan yang tidak
dikehendaki atau perbuatan yang salah (the prevention of crime or
undesired conduct or offending conduct);
2) untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si
pelanggar (the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for
perceived wrong doing).
Penentuan jenis dan ukuran sanksi pidana untuk suatu tindak pidana atau
kejahatan biasanya menggunakan asas kesetimpaian (proporsional).
Keharusan adanya asas kesetimpalan dalam menetapkan sanksi pidana
terhadap suatu tindak pidana atau kejahatan tercermin dalam filsafat
34 Fitzgerald, Criminal Law and Punishment, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hal. 98. 35 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hal. 6.
43
, Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
Beccaria yaitu let the punishment fit the crime (sanksi pidana harus sesuai
dengan kejahatan). Skala keadilan tidak ditergantungkan pada prasangka
prasangka perseorangan (personal prejudices), yang bersifat buta36.
Adanya kesetimpalan antara kejahatan dan pidana menimbulkan adanya
differensiasi pidana antara delik yang satu dengan delik yang lain. Penetapan
sanksi pidana dengan asas kesetimpalan ini dipandang sebagai cara yang
efektif untuk menanggulangi gejala kejahatan37.
Asas kesetimpalan ini mempunyai hubungan yang erat dengan klasifikasi
kejahatan. Artinya, klasifikasi keseriusan kejahatan menentukan berat
ringannya sanksi pidana. Klasifikasi kejahatan yang sangat berat diancam
dengan pidana yang sangat berat, kejahatan berat diancam dengan sanksi
pidana berat, kejahatan ringan diancam dengan sanksi pidana ringan, dan
kejahatan yang sangat ringan diancam dengan sanksi pidana sangat ringan.
Karena arti penting klasifikasi kejahatan, ada yang berpandangan bahwa
langkah pertama dalam program pengkajian dan pengevaluasian hukum
pidana adalah memilih seperangkat kategori untuk mengklasifikasikan
kejahatan38.
Mengenai klasifikasi kejahatan dapat ditinjau dari berbagai sudut
pandang, antara lain kejahatan sebagai masalah sosial legal (legal-social
problem) yang diklasifikasikan berdasarkan39:
1. Berat ringannya;
2. Mereka yang dirugikan, dapat dibagi dalam :
kejahatan yang merugikan individu, misalnya pembunuhan, perkosaan,
pencurian, perampokan dan lain-lain;
36 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hal. 29. 37 Roeslan Saleh, Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana, Jakarta,
Aksara Baru, 1985, hal. 66. 38 Sanford H. Kadish (Ed), Encyclopaedia of Crime and Justice, Volume 1, London, Collier Macmillan
Publication Co, 1990, hal. 515. 39 Purnianti dan Moh. Kemal Darmawan, Mazhab dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi, Bandung,
Citra Aditya Bakti, 1994, hal. 9. 44
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan don Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
a. kejahatan yang merugikan negara, antara lain terdiri dari kejahatan
terhadap keagungan (dignity) dan keamanan negara (security);
b. kejahatan yang merugikan (terhadap) kesejahteraan sosial (social
welfare) 1 misalnya tidak membayar pajak pendapatan, melarikan mobil
dengan kecepatan maksimum, tindak pidana ekonomi; mengenai
perkembangan kejahatan ini asumsinya adalah makin maju
masyarakatnya maka makin banyak aturan-aturan yang menjaga
kesejahteraan sosial masyarakat tersebut;
3. Kejahatan yang tradisional atau kejahatan kontemporer (konsep baru).
Kejahatan-kejahatan yang tradisional adalah yang memang sejak dulu
sudah dirasakan sebagai perbuatan-perbuatan yang merugikan, tidak
patut dan menjengkelkan (seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan
dan sebagainya).
Hukum pidana Indonesia juga mengklasifikasikan tindak pidana dalam
kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen). Misalnya, Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi klasifikasi tindak pidana
menjadi kejahatan dan pelanggaran. KUHP terdiri dari 3 (tiga) Buku yaitu :
Buku Kesatu tentang Aturan Umum, Buku Kedua tentang Kejahatan dan
Buku Ketiga tentang Pelanggaran.
Sedangkan Rancangan KUHP Tahun 2004 tidak lagi mengklasifikasikan
tindak pidana ke dalam kejahatan . (misdrijjeven1 crimes) dan pelanggaran
(overtredingen1 infractions). Hal ini didasarkan bahwa mengingat dalam
sejarah perkembangan hukum pidana tidak ada definisi dan kriteria yang
jelas serta konsisten yang bersifat kualitatif, untuk membedakan antara
keduanya, sebagaimana terdapat di dalam sistem Anglo Saxon yang
merumuskannya sebagai ma/a in se (acts wrong in themselves) dan mala
prohibita (acts wrong because they are prohibited). Semua perbuatan
melawan hukum yang dirumuskan dalam Rancangan KUHP dicakup dengan
istilah merupakan "Tindak Pidana". Dengan demikian Rancangan KUHP
45
., Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
hanya mengatur 2 (dua) buku yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum dan
Buku II tentang Tindak Pidana40.
Penggolongan kejahatan dapat pula berdasarkan tingkat kerugian yang
ditimbulkannya. Kejahatan dapat mendatangkan berbagai jenis kerugian bagi
kehidupan manusia (korban) yang meliputi : kerugian materi (uang),
penderitaan fisik (Iuka atau cacat), kehilangan nama baik, dan kehilangan
nyawa.
Pada prakteknya dalam pembentukan perundang-undangan, gradasi
keseriusan kejahatan berdasarkan kerugian yang ditimbulkannya ternyata
tidak ada kesatuan pendapat di kalangan para ahli. Kongres PBB ke-6 Tahun
1980 di Caracas mengenai Prevention of Crime and Treatment of Offender,
menegaskan bahwa kejahatan-kejahatan yang sangat membahayakan dan
merugikan tidaklah hanya kejahatan-kejahatan terhadap nyawa, orang dan
harta benda, tetapi juga penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)41•
Menurut Peter, kejahatan memang merugikan masyarakat, tetapi tidaklah
benar bahwa besarnya kerugian yang disebabkannya berhubungan secara
teratur dengan intensitas penekanan yang ditimbulkannya. Mengenai
kejahatan serius Peter mengemukakan sebagai berikut42:
Di dalam hukum pidana kebanyakan bangsa beradab, pembunuhan
dimanapun dianggap sebagai kejahatan terbesar. Tetapi, krisis ekonomi,
ambruknya pasaran efek-efek, bahkan suatu kegagalan, dapat membuat
suatu organisasi sosial menjadi berantakan demikian seriusnya sehingga
melebihi suatu pembunuhan itu sendiri. Tidak perlu disangsikan bahwa
pembunuhan selamanya merupakan kejahatan, tetapi tidak ada bukti bahwa
pembunuhan merupakan kejahatan terbesar. Apa artinya kurang satu
40 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tahun 2004, hal. 2-3.
41 Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hal. 16. 42 A.AG. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan Sosial - Buku teks Sosiologi
Hukum Buku Ill, Jakarta, Sinar Harapan, 1990, hal. 42. 46
, Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
nyawa bagi masyarakat? Apa artinya satu sel yang hilang bagi organisme?
Kita mengatakan bahwa keselamatan umum dimasa depan akan terancam
jika tindakan itu tidak dihukum; tetapi jikalau kita membandingkan arti bahaya
itu, walaupun memang nyata, dan arti hukumannya, tiadanya keseimbangan
tampak menyolok. Selain itu, contoh-contoh yang baru kita sebut
menunjukkan bahwa suatu tindakan bisa mengakibatkan malapetaka bagi
masyarakat tanpa mendatangkan tindakan penumpasan apa pun. Maka
definisi kejahatan ini sama sekali tidak memadai.
Kerugian materiil akibat kejahatan dapat dibedakan menjadi biaya
langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Mengenai hal
ini ekonom Thomas C. Schelling menyarankan bahwa kita harus melihat
biaya langsung dan biaya tidak langsung kejahatan supaya mendapatkan
suatu ide yang jelas mengenai apakah yang harus dilakukan untuk
mengurangi kejahatan dan siapa akan diuntungkan dari pengurangan
tersebut. Dia mengemukakan bahwa jika kita harus mengurangi semua
kejahatan melalui ukuran keamanan dan praktik penegakan hukum, biaya
langsung kejahatan akan menjadi nol, tapi biaya hidup dalam suatu
lingkungan potensial kejahatan akan menjadi besar. Karena jalan akan
kosong, tidak akan ada kejahatan jalanan, tetapi biaya kesempatan bagi
mereka yang tinggal di rumah akan besar43•
Kejahatan terorganisasi menimbulkan kerugian yang sangat besar
terhadap masyarakat. Hasil yang diperoleh kejahatan terorganisasi melalui
barang-barang ilegal dan jasa hampir mencapai dua kali lipat keuntungan
uang dari gabungan aktivitas kriminal lainnya. Meskipun mendatangkan
banyak kerugian, fakta ini tidak menimbulkan kesadaran untuk menempatkan
kejahatan terorganisasi sebagai kejahatan serius44.
Asas kesetimpalan mempunyai pengaruh yang besar dalam pemikiran
hukum pidana, khususnya dalam penetapan sanksi pidana terhadap tindak
43 John E. Concklin, The Impact of Crime, New York, Macmillan Publishing Co. Inc., 1975, hal. 4-5. 44 Ibid.
47
.. ,Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pemba/akan liar-2008
pitj~'!C!~_Q!eh karena itu, asas ini kemudian menjadi asas yang fundame~tal
dalam menetapkan sanksi pidana. Selain itu, asas kesetimpalan memainkan
peranan penting dalam penetapan sanksi pidana yang diancamkan terhadap
tindak pidana dalam praktek perundang-undangan. Penerapan a$as
kesetimpalan dalam praktek perundang-undangan melahirkan hubungan
simbiotis antara tindak pidana dengan sanksi pidana. Artinya, gradasi
keseriusan kejahatan mempengaruhi berat ringannya sanksi pidana a~au
berat ringannya sanksi pidana mencerminkan gradasi keseriusan kejahatan.
Meskipun asas kesetimpalan ini mempunyai pengaruh yang kuat dalam
pemikiran hukum pidana, namun menurut Abdullah Ahmed An Nairn, dal~m
prakteknya sulit untuk mengukur berat ringannya sanksi pidana yang ak.an
diancamkan terhadap suatu tindak pidana. Menurut Ahmed, sangat sulit
untuk menentukan batas-batas kekejaman atau ketidakmanusiawian
hukuman dan perlakuan terhadap orang-orang yang telah melakukan tindak
pidana 45.
Selain karena kesulitan mengukur berat ringannya sanksi pidana yang
akan diancamkan terhadap suatu tindak pidana, kesulitan lain yang muncul
dalam penerapan asas kesetimpalan adalah kesulitan mengukur gradej)Si
seriusitas kejahatan. Bahkan menurut Middendorf, tidak ada hubungan logis I
antara kejahatan dengan jumlah lamanya pidana karena penggunaan sanksi
pidana, pada kenyataannya kurang efektif untuk menanggulangi kejahatan
dan untuk memperbaiki perilaku terpidana. Sebaliknya, sanksi pidana yang
berat dan kejam sering membawa dampak negatif terhadap perilaku dan
sikap mental terpidana46.
Pertanggungjawaban seseorang berdasar kesalahan harus diganti I
dengan sifat berbahayanya si pembuat. Bentuk pertanggungjawaban kepada I
si pembuat lebih bersifat tindakan untuk perlindungan masyarakat. Dalam Hal I
I
45 Abdullah Ahmed An Nairn, Dekonstruksi Syari'ah, Yogyakarta, LKIS dan Pustaka Pelajar, 1990, hal. 198.
46 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang, CV Ananta, 1994, hal. 115.
48
.. .. ,Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan don Pemberantasan Pemba/akan Liar-2008
ini, jika menggunakan istilah pidana maka harus tetap diorientasikan pada
sifat-sifat si pembuat sehingga terdapat individualisasi pidana yang bertujuan
mengadakan resosialisasi si pembuat47.
Penentuan berat ringannya sanksi pidana yang diancamkan terhadap
tindak pidana bukan hanya didasarkan pada pertimbangan ketercelaan nilai
moral perbuatan, tetapi juga didasarkan pada penilaian besarnya kerugian
yang menimpa kepentingan individu dan masyarakat48.
Tingkat keseriusan kejahatan dipengaruhi pula oleh sikap batin pelaku.
Menurut Wezel yang terkenal dengan ajaran Finale Handlungslehre, sikap
batin pelaku merupakan unsur tindak pidana. Menurut ajaran Finale
Handlungslehre, perbuatan merupakan satu-satunya objek hukum pidana.
Perbuatan mempunyai struktur yang bersifat final atau intensionil, berbeda
dari proses yang berjalan secara kausal. Perbuatan adalah kelakuan yang
dikendalikan secara sadar oleh kehendak yang diarahkan kepada akibat
akibat tertentu49.
Selanjutnya mengenai jenis-jenis pidana sendiri, berdasarkan hukum
pidana positif (KUHP dan di luar KUHP) terdapat adanya pidana pokok dan
pidana tambahan. Pasal 10 KUHP menentukan bahwa pidana terdiri atas:
1) pidana pokok: pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana
denda; pidana tutupan.
2) pidana tambahan: pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang
barang tertentu; pengumuman putusan hakim.
Mengingat pembalakan liar sudah menimbulkan kerugian dan bahaya
bagi terpeliharanya ekosistem yang menimbulkan bahaya pula bagi manusia
berupa kerawanan bencana alam serta menimbulkan kerugian terhadap
kekayaan negara dalam jumlah yang sangat besar, termasuk biaya untuk
melakukan rehabilitasi hutan/reboisasi. Maka berdasarkan uraian mengenai
47 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hal. 32. 48 Abdullah Ahmed An Nairn, Op. Cit., hal. 113-114. 49 Roeslan Saleh, Op. Cit, hal. 18.
49
. NQskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan liar-2008
tujuan politik kriminil serta penentuan jenis dan ukuran sanksi pidana untuk
suatu tindak pidana, dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus
pembalakan liar, perlu dirumuskan adanya :
1) Sanksi pidana pokok berupa: sanksi pidana mati, penjara dan/atau denda.
Baik sanksi pidana penjara maupun sanksi pidana denda perlu
dirumus~an sanksi minimal dan sanksi maksimal.
2) Sanksi pidana tambahan berupa: pencabutan hak tertentu; perampasan
hasil tindak pidana; pengumuman putusan hakim; dan/atau pembayaran
ganti kerugian.
Dalam hal kegiatan pembalakan liar dilakukan oleh badan hukum atau
korporasi, selain dikenai sanksi pidana, juga dikenai sanksi administratif
berupa:
b. paksaan pemerintah;
c. uang paksa; dan/atau
d. pencabutan izin
D. UPAYA MENGATASI PEMBALAKAN LIAR
Menyadari bahwa pembalakan liar adalah permasalahan yang kompleks,
tidak hanya sebatas pada permasalahan penegakan hukum, maka upaya untuk
mengatasi pembalakan liar dilakukan secara komprehensif. Secara garis besar
upaya pendekatan yang dilakukan untuk melindungi kelestarian sumber daya
hutan dari praktek pembalakan liar dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan
dan pendekatan keamanan. so
Pendekatan kesejahteraan dilakukan dengan cara menggalang kekuatan
dari masyarakat sekitar hutan untuk menolak pembalakan liar. Masyarakat
sekitar hutan merupakan gerbang utama dan lokomotif dari praktek pembalakan
50 Rahmi Hidayati D, dkk, 2006, Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan, Wana Aksara, Banten, hal.16
50
, Nqskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pemba/akan Liar-2008
liar. Adapun permasalahan utama masyarakat mau terlibat dalam pembalakan
l,iar adalah karena kemiskinan. Fakta menyebutkan bahwa dari 48,8 juta
masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, lebih dari 10,2 juta
diantaranya tergolong dalam kategori miskin. Bahkan mengacu data terakhir
dengan mengambil sampel di 7 propinsi diperkir~kan 38,5 juta orang yang
berkategori miskin tinggal di sekitar dan di dalam hutan. 51 Data ini mencerminkan
sebuah anomali. Bagaimanapun sumber daya hutan beserta segala kekayaan
alamnya merupakan sumber daya alam yang sangat kaya dengan berbagai
potensi ekonomi bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan
masyarakat. Utamanya masyarakat yang hidup dan tinggal di dalam dan di
sekitar hutan. Di sisi lain, kebijakan kehutanan pemerintah yang lebih ke arah
industrialisasi kehutanan, telah meminggirkan masyarakat desa hutan. Akibatnya
akses mereka akan hutan melemah, dan ini berarti hilangnya penguasaan
"asset" atas sumber daya hutan, dan berarti juga hilangnya mata pencaharian
mereka. Kondisi ini menyeret mereka dalam salah satu mata rantai praktek
pembalakan liar.
Sebenarnya praktek pembalakan liar bertentangan dengan sistem dan
tata nilai yang selama ini diterapkan dalam kehidupan masyarakat desa hutan.
Secara historis kultural masyarakat desa hutan adalah bagian integral dari
ekosistem hutan. Oleh karena tingkat kesejahteraan masyarakat desa hutan
yang tercermin dari tingginya kualitas hidup masyarakat merupakan salah satu
benteng utama bagi terwujudnya kelestarian hutan. Sebaliknya rendahnya
tingkat kesejahteraan masyarakat desa hutan yang tercermin dari kemiskinan
masyarakat merupakan ancaman paling utama dari kelestarian hutan. Karena
kondisi mereka ini akan dimanfaatkan para pemilik modal yang hanya ingin
mengeruk keuntungan dalam jangka pendek dari sumber daya hutan dengan
mengeksploitasi kemiskinan mereka.
51 Lihat dokumen Revitalisasi Kehutanan, Kadin Indonesia, 2005, Jakarta 51
.Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pemba/akan Liar-2008
D~r:igan demikian, kunci keberhasilan mengatasi pembalakan liar adalah
bagaimana para pihak membangun benteng pertahanan yang kuat sehingga
praktek pembalakan liar tersebut tidak bisa masuk apalagi merambah kawasan
hutan yang sudah memiliki pengaman yang tangguh.52 Benteng tersebut adalah
masyarakat desa hutan.53 Kokohnya benteng tersebut tercermin pada tingkat
kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Untuk mempertinggi tingkat
kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa hutan dilakukan melalui
upaya pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat desa hutan ini paling tidak
menurut Robert Dahl (1963) "would have be having or being given power to
influence or controf', sehingga setiap individu mempunyai pilihan dan kontrol
pada semua aspek kehidupan sehari-harinya seperti pekerjaan mereka, akses
terhadap sumber daya, partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, dan lain
sebagainya. 54
Pemberdayaan masyarakat juga paling tidak harus mampu meningkatkan
kemampuan individu untuk mengembangkan kemampuan diri dalam meniti
kehidupan bermasyarakat. Ada tiga strategi yang harus dilakukan dalam rangka
pemberdayaan masyarakat. Pertama, menciptakan iklim yang memungkinkan
potensi masyarakat berkembang. Kedua,memperkuat potensi atau daya yang
dimiliki masyarakat. Ketiga, memberdayakan dalam arti melindungi, yaitu
dihindari sejauh mungkin proses membuat pihak yang lemah semakin lemah.55
Pendekatan lain yang digunakan untuk mengatasi pembalakan liar adalah
pendekatan keamanan. Pendekatan keamanan bersifat kuratif diperlukan untuk
52 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, setiap pemegang izin pemanfaatan hutan mempunyai kewajiban membangun batas hutan dan melakukan perlindungan hutan di areal kerjanya.
53 Ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk masyarakat desa hutan, seperti masyarakat sekitar hutan, masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan, masyarakat pedalaman, masyarakat hutan adat. Namun kesemuanya memiliki kesamaan yaitu memiliki keterikatan yang tinggi dengan hutan, baik dalam kehidupan perekonomian maupun kehidupan sosial budaya mereka. 54 Lihat Priyono dan Pranarka (penyunting), Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan /mplementasi, Jakarta:CSIS, 1996, ha163 55 Lihat Agung Nugraha, Murtijo., 2005, Antropologi Kehutanan, Wana Aksara, Banten, Indonesia, hal. 149
52
·. ,Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
memberikan kepastian hukum dan penegakan hukum. Pendekatan keamanan
dilakukan terkait dengan penyimpangan peraturan perundang-undangan
(khususnya peraturan di bidang kehutanan), baik menyangkut perizinan,
keberadaan dokumen hasil hutan, proses pengangkutan, hingga
pemanfaatannya. Praktek pembalakan liar menunjukkan perkembangan yang
mengarah pada terbangunnya suatu bentuk jaringan yang relatif luas, kuat, dan
mapan baik yang melibatkan para pihak di dalam dan di luar negeri. Mengingat
kayu merupakan komoditas yang paling mudah menghasilkan uang dan paling
mudah untuk mendapatkan keuntungan besar secara cepat dengan biaya relatif
murah. Keuntungan tersebut meskipun dengan tingkat distribusi tidak merata
namun dapat menyebar ke semua pihak yang terlibat, mulai buruh, pemodal,
pengusaha sampai oknum pejabat pemerintah terlibat dalam praktek
pengusahaan hasil hutan kayu.
Menyadari kompleksnya permasalahan pembalakan liar di Indonesia,
upaya penanganan melalui dua pendekatan di atas perlu ditambahkan dengan
melakukan upaya yang sifatnya mendesak (dilakukan untuk jangka pendek).
Pertama, Mengembangkan rencana rasionalisasi industri pengolahan kayu yang
menyeluruh dan komprehensif di mana rencana ini akan mengidentifikasi dan
memberikan mandat terhadap upaya pengurangan konsumsi kayu bulat secara
bertahap guna menyeimbangkan permintaan dengan pasokan kayu legal.
Rencana ini juga menggambarkan upaya-upaya untuk memberikan kompensasi,
memberi pelatihan lagi atau menyediakan sarana pekerjaan baru bagi orang
orang yang kehilangan pekerjaannya akibat rencana restrukturisasi tersebut,
serta mengidentifikasi alternatif baru pasokan kayu.
Kedua, Menurunkan permintaan akan kayu ilegal dan merancang
permintaan akan produksi dan perdagangan kayu legal dengan cara:
membangun kesepakatan bilateral dan multilateral agar pembelian dan import
kayu ilegal menjadi 'legal' di negara konsumen, menetapkan suatu definisi kayu
legal yang jelas dan bersifat komprehensif, mengembangkan sistem verifikasi
53
, Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan don Pemberantasan Pemba/akan Liar-2008
dengan biaya rendah, membuat kerjasama dengan mitra perdagangan
internasional agar mereka hanya mengimpor kayu legal dan mendorong produksi
kayu legal yang berkesinambungan.
Ketiga, Memperbaiki tata kelola, transparansi dan akuntabilitas melalui
serangkaian upaya-upaya yang bertujuan untuk memberantas korupsi. Upaya
awal yang baik untuk diterapkan adalah dengan: memperbaiki sistem distribusi
SKSHH untuk memberantas distribusinya di pasar gelap; menurunkan jumlah
persyaratan administratif dan teknis yang membuka kesempatan bagi aparat
pemerintah dan aparat keamanan untuk mendapatkan pungutan liar ,
menghapuskan pungutan liar, menghapuskan korupsi di kalangan elit dengan
cara membatasi kepemilikan HPH dan HTI bagi aparat pemerintahan pada level
atas. Usaha ini juga dijalankan dengan memperbaiki mekanisme akuntabilitas
pada tingkat kabupaten dan mendukung organisasi pengawas yang dibentuk
oleh masyarakat madani.
Keempat, Menyelaraskan perbedaan diantara institusi/lembaga
pemerintah untuk mengklarifikasi peranan dan kewenangan berbagai tingkatan
pemerintahan di bidang pengelolaan hutan dengan cara memperbaiki
komunikasi, merevisi legislasi yang tidak jelas dan kontradiktif yang
memungkinkan interpretasi hukum yang bebas dan tidak jelas serta
meningkatkan pemahaman mengenai keuntungan ekonomis dan jasa sosial
yang bisa didapatkan dari pengelolaan hutan yang lestari. Kelima, Meningkatkan
jaminan kepemilikan tanah bagi masyarakat lokal dan mendorong partisipasi aktif
di bidang pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial agar masyarakat
lokal memiliki kepentingan dalam pengamanan hutan.
Upaya mengatasi pembalakan liar adalah tanggung jawab bersama. Yaitu
tanggung jawab dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, maupun
masyarakat sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Agar upaya
mengatasi pembalakan liar ini dapat berjalan optimal, koordinasi dan kerjasama
tiiap pihak sangat diperlukan.
54
· ·. ·. Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
BABIV
RUANG LINGKUP NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PEMBALAKAN LIAR
A. Materi Muatan Rancangan Undang-Undang
Materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang
tentang Pencegahan dan Pembalakan Liar ini secara umum menjawab
permasalahan seputar upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar,
kelembagaan dan koordinasi antar pelaksana dan penanggungjawab program
pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar serta bagaimana sistem
pemberian sanksi yang efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku
pembalakan liar. Dalam upaya pencegahan, diatur mengenai kebijakan yang
bersifat sementara (temperer) dan mendesak untuk dilaksanakan guna
menunjang terlaksananya upaya-upaya pencegahan pembalakan liar. Kebijakan
tersebut berskala nasional dan mengacu pada target-target sasaran dengan
jangka waktu tertentu dengan tujuan menyeimbangkan kondisi industri dan
pasokan kayu legal. Selain itu terdapat upaya pencegahan yang bersifat
berkesinambungan seperti kegiatan-kegiatan dalam rangka menghilangkan
kesempatan timbulnya pembalakan liar itu sendiri terkait dengan penjagaan
kawasan hutan. usaha pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan juga
merupakan salah satu upaya pencegahan yang dilaksanakan secara terus
menerus dan berkesinambungan.
Adapun upaya pemberantasan pembalakan liar merupakan upaya atau
penindakan secara hukum terhadap pelaku pembalakan liar. Rancangan
undang-Undang ini menyiapkan perangkat hukum materiil yang memuat jenis
jenis kegiatan pembalakan liar baik secara langsung maupun tidak langsung,
melibatkan pejabat atau perseorangan, dengan pelaku individu maupun badan
hukum termasuk korporasi. Selain itu pada bab pemberantasan ini diatur pula
mengenai hukum formil sebagai landasan beracara dalam menyelesaikan
SS
., Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
perkara pembalakan liar muali dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di
siding pengadilan. Sebagai rujukan, RUU ini juga memuat ketentuan pidana
yang memiliki disparitas dalam penetapan berat ringannya hukuman sesuai
dengan tingkat kejahatan dan faktor-faktor pemberat dan peringan hukuman.
Sebagai pelaksana dan penanggung jawab secara nasional dari berbagai
upaya dan program pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar, RUU ini
mengamanatkan dibentuknya suatu tim koordinasi yang pada praktiknya
bukanlah suatu lembaga baru tetapi lebih pada mengefektifkan koordinasi dari
beberapa instansi terkait dibawah satu atap koordinasi. Tim ini berada di pusat
dan daerah tingkat provinsi. Guna mengefektifkan upaya pencegahan dan
pemberantasan pembalakan liar, tim tersebut diberi beberapa tugas dan
kewenangan. RUU ini dilengkapi pula dengan pengaturan mengenai bagaimana
masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan
pembalakan liar, bentuk-bentuk kerjasama internasional yang dapat dilakukan
guna mendorong dan mensukseskan upaya pencegahan dan pemberantasan
pembalakan liar dengan melibatkan dunia internasional secara aktif. Dalam
rangka memberikan jaminan bagi pihak-pihak yang berjasa dalam membantu
upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar diatur pula ketentuan
mengenai pembiayaan dan insentif. Sedangkan bagi masyarakat yang bertindak
baik sebagai pelapor, informan maupun saksi, RUU ini juga mengatur tentang
perlindungan keamanan dan hukum bagi mereka beserta keluarga.
Secara berurutan, materi muatan dari RUU tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Pembalakan Liar ini mengatur tentang:
1. Konsiderans.
Konsiderans menimbang merupakan intisari dari landasan pemikiran yang
merupakan dasar filosofis, sosiologis dan yuridis dari pembentukan
Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Pembalakan Liar.
56
., Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
2. Dasar Hukum Mengingat.
Dasar hukum mengingat memuat dasar kewenangan pembentukan
Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Pembalakan Liar yakni Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 28H ayat (1 ), Pasal 33
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
serta Undang-Undang yang memerintahkan dan terkait langsung dengan
pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Pembalakan Liar yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
3. Ketentuan Umum.
Ketentuan umum dalam Rancangan Undang-Undang tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar berisi batasan pengertian
dan definisi dari beberapa istilah yang digunakan dalam rancangan undang
undang yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya, disebut secara berulang
ulang dan membutuhkan pengertian atau batasan yang jelas. Ketentuan
umum disusun secara berurut dari norma yang bersifat umum kepada yang
khusus dan dari norma yang diatur lebih dahulu dalam pasal. Ketentuan
umum tersebut antara lain:
a. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber
daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komoditas alam
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan .
. b. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan
oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan
tetap.
c. Pembalakan liar adalah kegiatan pemanfaatan hutan secara tidak sah,
yang meliputi proses perizinan pemanfaatan hutan, penebangan,
57
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
pengangkutan, peredaran, penyelundupan, penjualan, danlatau
pemanfaatan kayu lebih lanjut.
d. Pencegahan pembalakan liar adalah segala upaya yang dilakukan untuk
menghilangkan kesempatan terjadinya pembalakan liar.
e. Pemberantasan pembalakan liar adalah segala upaya yang dilakukan
untuk menindak secara hukum pelaku pembalakan liar langsung atau
tidak langsung atau yang terkait lainnya.
f. Penyuluhan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku
masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan.
g. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan,
memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan
bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara
optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga
kelestariannya.
h. lnsentif adalah pemberian sesuatu yang mempunyai nilai terhadap jasa
perseorangan, masyarakat, badan hukum, korporasi, dan/atau Pemerintah
Daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar.
4. Asas dan Tujuan
Upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar berlandaskan
pada asas-asas:
a. tanggung jawab negara;
b. keberlanjutan;
c. keadilan dan kepastian hukum;
d. bertanggung gugat;
e. prioritas; dan
f. keterpaduan dan koordinasi.
58
. Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
Adapun tujuan dari upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan
liar:
a. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga
kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
b. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan
memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat
sejahtera;
c. meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan
pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan
pembalakan liar; dan
d. memberikan efek jera bagi pelaku pembalakan liar.
5. Pencegahan Pembalakan Liar
Pencegahan pembalakan liar dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah
daerah, selain itu masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang
memperoleh izin pemanfaatan hutan juga dapat ikut berpartisipasi dalam
pencegahan pembalakan liiar.
Dalam rangka pencegahan pembalakan liar Pemerintah membuat
kebijakan berupa:
a. rasionalisasi industri pengolahan kayu;
b. penetapan sumber kayu alternatif;
c. promosi dan perlindungan perdagangan kayu legal;
d. perbaikan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dibidang kehutanan;
dan
e. klarifikasi peranan dan kewenangan dari berbagai tingkatan pemerintahan
di bidang pengelolaan hutan.
Selain membuat kebijakan, usaha pencegahan pembalakan liar dilakukan
dengan menghilangkan kesempatan timbulnya pembalakan liar,
pemberdayaan masyarakat, dan penyuluhan. Untuk menghilangkan
kesempatan timbulnya pembalakan liar dilakukan melalui kegiatan:
59
· ... Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
a. pemantapan kawasan hutan;
b. menjaga kawasan hutan dan hasil hutan;
c. patroli;
d. koordinasi ;
e. meningkatkan kapasitas jaringan informasi;
f. meningkatkan produktivitas masyarakat;
g. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat; dan
h. mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat.
Sedangkan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui:
a. membentuk hutan desa;
b. membentuk hutan kemasyarakatan; atau
c. membangun kemitraan.
6. Pemberantasan Pembalakan Liar.
Pemberantasan pembalakan liar dilakukan dengan cara menindak
secara hukum pelaku pembalakan liar langsung, tidak langsung, atau yang
melibatkan pejabat. Tindakan secara hukum meliputi penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Mengingat kekhususan dari perkara
pembalakan liar, selain mengacu pada KUHAP, RUU ini membuat beberapa
aturan khusus yang mengesampingkan ketentuan hukum acara pidana yang
berlaku. Perkara pembalakan liar termasuk perkara yang didahulukan dari
perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian
secepatnya (asas prioritas).
Bab pemberantasan ini memuat norma-norma larangan mengenai
kategori dan jenis kegiatan pembalakan liar dari hulu sampai hilir, kegiatan
yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dan keterlibatan pejabat
baik secara langsung langsung maupun tidak langsung dengan pelaku
individu, pejabat maupun badan hukum termasuk korporasi. Pada bagian
60
.. Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
selanjutnya diatur mengenai hukum acara menyangkut proses dan
mekanisme penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
1) Kegiatan pembalakan liar (secara llansung) meliputi:
a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak
sesuai izin pemanfaatan hutan;
b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki
izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak
sah;
d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai,
dan/atau memiliki hasH pembalakan liar;
e. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau
patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam
kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang,
memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin
pejabat yang berwenang;
g. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil
pembalakan liar;
h. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau menyelundupkan
kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia melalui darat, perairan atau udara; dan/atau
i. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan,
dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal
dari pembalakan liar.
2) Kegiatan pembalakan liar (secara tidak langsung) meliputi:
a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar;
b. turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar;
61
. · Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
c. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar;
d. mendanai pembalakan liar secara langsung atau tidak langsung;
e. menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
f. mencuci kayu hasil pembalakan liar seolah-olah menjadi kayu yang
sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar
negeri;
g. menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan,
menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar
negeri, dan/atau menukarkan yang diketahuinya atau patut diduga
merupakan hasil pembalakan liar; dan/atau
h. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui
atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar sehingga seolah
olah menjadi harta kekayaan yang sah.
3) Kegiatan pembalakan liar yang melibatkan pejabat antara lain:
a. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan yang tidak
sesuaikewenangnya;
b. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan yang yang
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melindungi pelaku pembalakan liar;
d. turut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar;
e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar;
f. menerbitkan SKSHH tanpa hak; dan/atau
g. melakukan pembiaran dan/atau kelalaian dalam melaksanakan tugas.
4) Kegiatan lain yang terkait proses pembalakan liar:
a. mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara langsung
maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar.
62
, N9skah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
b. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar yang berasal dari kawasan
konservasi.
c. menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak
pidana pembalakan liar.
d. melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan
petugas yang mellakukan pencegahan dan pemberantasan
pembalakan liar
e. memalsukan surat izin pemanfaatan hutan.
f. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hutan
g. memalsukan SKSHH.
h. menggunakan SKSHH palsu
i. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan hutan
yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
j. merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan yang terkait
dengan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar
k. merusak, memindahkan dan menghilangkan pal batas hutan dengan
negara lain.
Pada bagian hukum acara menyangkut proses dan mekanisme
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilan memuat
mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam
kepentingan proses beracara tersebut, jangka waktu penyelesaian perkara,
alat bukti, penyitaan dan penyimpanan barang sitaan dan proses berpekara
di siding pengadilan.
Dalam rangka penyidikan, RUU ini memberikan kewenangan kepada
PPNS sebagai berikut:
63
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan
berkenaan dengan tindak pidana pembalakan liar;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang
diduga melakukan tindak pidana pembalakan liar;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum
sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pembalakan liar;
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana pembalakan liar;
e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan
bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat
dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana pembalakan liar; dan
f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana pembalakan liar.
Selain itu untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di
sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang :
a. meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka
atau terdakwa.
b. meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik
tersangka atau terdakwa yang diduga sebagai hasil penebangan liar.
c. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa
kepada unit kerja terkait.
d. meminta bantuan kepada Pusat dan Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan untuk melakukan penyelidikan atau data keuangan tersangka.
e. menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dimasukkan dalam daftar
pencarian orang;
f. meminta kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan
sementara tersangka dari jabatannya.
64
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
Adapun alat bukti dalam pemeriksaan perkara pembalakan liar, meliputi:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana;
b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau
disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
dan/atau
c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau
didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu
sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain
kertas, atau yang terekam secara elektronik, berupa:
1) tulisan, suara atau gambar;
2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan/atau
huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau
dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau
memahaminya
Adapun penyelesaian perkara pembalakan liar di tingkat penyidikan
adalah 45 (empat puluh lima) hari sejak dimulainya penyidikan dan
tambahan 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan lanjutan. Sedangkan di
tingkat pengadilan perkara pembalakan liar diperiksa dan diputus oleh
pengadilan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak
tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum. Untuk
banding, diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 40 (empat
puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh
Pengadilan Tinggi. Untuk kasasi, diperiksa dan diputus dalam jangka waktu
paling lama 50 (lima puluh hari) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas
perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
65
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
7. Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Pembalaka Liar
RUU ini mengamanatkan pembentukan suatu sistem koordinasi dalam
upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar secara fungsional
dan terkoordinasi lintas departemen dan instansi pemerintahan, baik di
tingkat Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi. Dalam pelaksanaannya,
Presiden membentuk Tim Koordinasi P3L yang dikoordinasikan oleh Menteri
Koordinator Politik dan Keamanan dan Menteri Kehutanan dengan
mengendalikan departemen dan badan-badan terkait di bidang:
a. kehutanan;
b. lingkungan hidup;
c. pemerintahan dalam negeri;
d. hubungan luar negeri;
e. sosial;
f. pengembangan usaha kecil menengah;
g. ketenagakerjaan;
h. perdagangan;
i. perindustrian;
j. pertanian;
k. keuangan;
I. perhubungan;
m. pertahanan dan keamanan;
n. Kepolisian Negara RepubHk Indonesia;
o. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
p. Tentara Nasional Indonesia;
q. Badan lntelijen Negara; dan
r. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Tim Koordinasi P3L memiliki tugas:
a. mengkoordinasikan instansi yang terkait dalam penyusunan kebijakan dan
pelaksanaan di bidang pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar;
b. mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar;
66
.. Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
c. melaksanakan penegakan hukum pembalakan liar;
d. melaksanakan pembinaan pencegahan dan pemberantasan pembalakan
liar;
e. melaksanakan kerja sama internasional dalam pencegahan dan
pemberantasan pembalakan liar;
f. melaksanakan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi;
g. melaksanakan kerja sama dengan lembaga keuangan dalam rangka
pemberantasan pembalakan liar; dan
h. menetapkan sistem pelaporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan
pemberantasan pembalakan liar.
Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi P3L diberi wewenang:
a. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi
pencegahan pembalakan liar;
b. melaksanakan kampanye anti pembalakan liar;
c. membangun dan mengembangkan sistem informasi pencegahan dan
pemberantasan pembalakan liar;
d. membangun, mengembangkan, dan membina jejaring sosial anti
pembalakan liar;
e. melakukan kerja sama dengan para pihak terkait dalam kegiatan
pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar;
f. melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembalakan liar;
dan
g. memantau penanganan perkara pembalakan liar.
Dalam menjalankan tugasnya Tim P3L pusat berkewajiban memberikan
laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap 6 (enam) bulan sedangkan
Tim P3L daerah berkewajiban memberikan laporan kepada Tim P3L Pusat
setiap 3 (tiga) bulan.
67
. Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan don Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
8. Peran Serta Masyarakat
Kesadaran hukum masyarakat yang tinggi sangat menunjang upaya
penegakan hukum, karena masyarakat menyadari dan memahami hak dan
kewajibannya sebagai warga negara secara selaras, serasi dan seimbang.
Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat seperti itu mengarah pada dua
hal yakni pertama, kepatuhan terhadap hukum karena menyadari bahwa
pada dasarnya kehidupan yang tertib, teratur, aman dan tentram itu tidak
terlepas dari adanya hukum dan tegaknya hukum. Kedua, kemauan untuk
turut memikul tanggung jawab dalam menegakkan hukum karena menyadari
bahwa tegaknya hukum merupakan kepentingan dan keperluan bersama.
Dalam penegakkan hukum untuk memberantas kegiatan pembalakan liar
pihak yang berwenang, baik Dinas Kehutanan maupun Kepolisian setempat
banyak dibantu oleh masyarakat/partisipasi masyarakat melalui pemberian
informasi baik Iisan maupun tulisan (menggunakan SMS atau website),
Iaporan tertulis atau laporan dalam bentuk penyampaian pendapat. Peran
serta masyarakat tersebut merupakan respons batik terhadap dibukanya
akses informasi yang disediakan oleh Tim Koordinasi P3L untuk menerima
semua laporan dari masyarakat berkaitan dengan pemberantasan
pembalakan liar.
Cara lain yang dapat ditempuh oleh masyarakat dalam memberantas
pembalakan liar adalah dengan bergabung dengan Organisas/Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kehutanan atau
lingkungan hidup yang terdapat di daerah. Dengan demikian peran serta
masyarakat merupakan inti keberhasilan dalam memberantas penebangan
pohon di dalam hutan secara tidak sah dan dalam mengembalikan kualitas
hutan yang sudah rusak. Apabila ketiga fungsi hutan (fungsi ekonomi, fungsi
sosial, dan fungsi lingkungan) sudah berjalan sebagaimana mestinya, maka
masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan secara optimal sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan itu sendiri
68
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
9. Kerjasama lnternasional.
Menyadari bahwa isu pembalakan liar telah menjadi permasalahan global,
maka RUU ini merekomendasikan Pemerintah maupun pemerintah daerah
untuk melakukan kerjasama internasional baik di tingkat bilateral, regional
maupun multilateral dalam upaya pencegahan dan pemberantasan
pembalakan liar. Dalam upaya pencegahan terdapat beberapa bentuk
kerjasama yang mungkin dilakukan antara lain:
a. pelaksanaan konservasi;
b. pelaksanaan pengelolaan hutan yang berkelanjutan;
c. peningkatan forest carbon stock; dan
d. pemberdayaan masyarakat.
Sedangkan di bidang pemberantasan dan penegakan hukum, kerjasama
dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang sudah
mengatur hal tersebut mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam
hal ini pemerintah juga dapat berperan aktif dan melakukan tindakan atau
upaya hukum dalam hal terjadinya perkara timber money laundering yang
melibatkan Negara lain.
10. Pembiayaan dan Pemberian lnsentif
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-Undang ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, hasil lelang, dan sumber dana lainnya yang sah.
Kemudian Untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam
memberantas penebangan pohon di dalam hutan secara tidak sah, maka
masyarakat perlu digugah untuk terus berperan serta, caranya antara lain
dengan memberikan penghargaan (reward) kepada mereka. Pemberian
insentif ini juga berlaku bagi seluruh pihak yang berjasa dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan pembaiakan liar baik perseorangan, badan
69
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
hukum, pihak penegak hukum sendiri bahkan Pemerintah daerah yang dinilai
berhasil dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar
diberi insentif berupa hak anggaran tambahan.
11. Perlindungan Saksi, Pelapor dan lnforman.
Agar peran serta masyarakat dapat bermanfaat dan dilakukan secara
berkesinambungan, maka pihak berwenang harus segera menindaklanjuti
laporan tersebut, antara lain dengan melakukan pengecekan terhadap
kebenaran dari setiap iaporan tersebut. Masyarakat baik yang melapor,
menjadi saksi maupun informan juga harus dilindungi identitasnya demi
keselamatan hidupnya. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan
keamanan dan perlindungan hukum. Pelaksanaan dan mekanisme
perlindungan ini pada hakikatnya diatur sesuai peraturan perundang
undangan yang berlaku.
1!2. Ketentuan Pidana
Dalam menentukan besaran dan disparitas sanksi pidana terhadap tindak
pidana yang dilanggar telah dilakukan simulasi dan perbandingan dengen
beberapa peraturan perundang-undangan lain.
Mengingat rangkaian kegiatan pembalakan liar sendiri terdiri dari
beberapa kegiatan dan melibatkan beberapa macam pelaku maka setidaknya
terdapat tiga pengelompokan besar:
Untuk kategori pelanggaran terhadap norma larangan menyangkut
kegiatan pembalakan liar secara langsung yang dilakukan oleh setiap orang
baik perseorangan maupun badan hukum (baik yang berada di dalam atau di
luar wilayah Negara Republik Indonesia) dikenai pidana penjara mulai dari 1
(satu) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dengan denda mulai dari
Rp. 500 000 000,- sampai dengan Rp. 15 000 000 000,-. Adapun untuk
kategori pelanggaran terhadap norma larangan menyangkut kegiatan
pembalakan liar secara tidak langsung yang dilakukan oleh setiap orang baik
70
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan don Pemberantasan Pembalakan liar-2008
pe_r:s~o_r~n_g~n maupun badan hukum (baik yang berada di dalam atau di luar
wilayah Negara Republik Indonesia) dikenai pidana penjara mulai dari .1 O
(sepuluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun dengan denda
mulai dari Rp. 10 000 000 000,- sampai dengan Rp.100 000 000 OOd,-.
Dengan ketentuan bahwa selain sanksi pidana, bagi pelaku badan hukl)m
termasuk korporasi yang melakukan kegiatan pembalakan liar yang
menimbulkan kerusakan lingkungan dikenai pidana administratif berupa:
a. paksaan pemerintah;
b. uang paksa; dan/atau
c. pencabutan izin
Dalam hal pejabat melanggar norma larangan menyangkut penerbitan i~in
dan hal-hal yang terkait dengan kewenagannya dipidana dengan pidana
penjara mulai 1 (satu) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun, dengan denda mu!ai '
dari Rp. 500 000 000,- sampai dengan Rp.10 000 000 000,-. Sedangkan
pejabat yang melakukan kegiatan pembalakan liar baik langsung maupun
tidak langsung, pidanya diperberat 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidaha
pokoknya. Selain penjatuhan sanksi pidana, dikenakan juga uang pengga~ti,
dan apabila tidak terpenuhi, maka terdakwa dapat dikenakan hukuman
badan.
13. Ketentuan Peralihan
Untuk mengantisipasi kekosongan hukum akibat peralihan dari peratur~n
perundang-undangan yang lama, maka pada saat Undang-Undang ini mul,ai
berlaku, semua perkara tindak pidana pembalakan liar yang telah dilakukan
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan berdasarkan Undang
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tah~n
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) tet~p
dilanjutkan sampai memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan
hukum tetap.
71
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan don Pemberantasan Pemba/akan Liar-2008
14. Ketentuan Penutup
Selain menyatakan mulai berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan
penutup juga menyatakan tidak berlaku dan dicabutnya beberapa peraturan
perundang-undangan yang secara substansi sudah dirubah oleh Undang
Undang ini.
B. Usulan Sistematika Rancangan Undang-Undang
Naskah akademis ini mengusulkan sistematika RUU tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Pembalakan Liar sebagai berikut:
JUDUL RUU
Konsiderans Menimbang
Dasar Hukum Mengingat
Diktum persetujuan
BAB I: KETENTUAN UMUM
BAB II: ASAS DAN TUJUAN
BAB Ill: PENCEGAHAN PEMBALAKAN LIAR
Bagian Kesatu: Umum
Bagian Kedua: Kebijakan Pencegahan Pembalakan Liar
Bagian Ketiga: Upaya Pencegahan Pembalakan Liar
Bagian Keempat: Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan
Paragraf 1: um urn
Paragraf 2: Pemberdayaan Masyarakat
Paragrat 3: Penyuluhan
72
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pemba/akan Liar-2008
BAB IV: PEMBERANTASAN PEMBALAKAN LIAR
Bagian Kesatu: Umum
Bagian Kedua: Larangan
Bagian Ketiga: Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di
Sidang Pengadilan
Paragraf 1 : penyidikan dan Penuntutan
Paragraf 2·. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
BAB V: KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PEMBALAKAN LIAR
BAB VI: PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VII: KERJASAMA INTERNASIONAL
BAB VIII: PEMBIAYAAN DAN PEMBERIAN INSENTIF
Bagian Kesatu: Pembiayaan
Bagian Kedua: Pemberian lnsentif
BAB IX: PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DAN INFORMAN
BAB X: KETENTUAN PllDANA
BAB XI: KETENTUAN PERALIHAN
BABX: KETENTUANPENUTUP
73
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan don Pemberantasan Pemba/akan Liar-2008
BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan
pencegahan dan pemberantas pembalakan liar sebagai berikut :
'
1. Upaya yang komprehensif yang dilakukan dalam rangka pencegahan dc:tn
pemberantasan pembalakan liar dilakukan mulai dari upaya pencegah~n yakni dengan mengeluarkan kebijakan pencegahan yang sifatnya
mendesak dengan sasaran jangka pendek. Kebijakan-kebijakan ini terkait i
dengan pengamanan pasokan kayu legal di tingkat nasional melalui
rasionalisasi industri pengolahan kayu yang juga didukung dengan
kebijakan guna mengantisipasi akibat langsung dari kebijakan rasionalis~si
tersebut. Selain itu dilakukan pula upaya pencegahan pembalakan liar ya~g
dilakukan secara regular dan berkesinambungan untuk meghilangkc;m
kesempatan terjadinya pembalakan liar. Upaya ini meliputi penjagaan dan
pemantapan kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat serta
meningkatkan penyuluhan. Selain upaya pencegahan juga dilakukan upaya
pemberantasan yang dilakukan melalui penegakan hukum pemberantasan
pembalakan liar dengan membuat norma-norma larangan yaryg
menyangkut kegiatan pembalakan liar baik yang dilakukan oleh
perseorangan, badan hukum termasuk korporasi maupun pejabat yang
melakukan atau terlibat pembalakan liar. Upaya yang komprehensif ini juga
dilengkapi dengan pengaturan mengenai hukum acara mulai dari hukum
acara penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Upaya lain yang dilakukan adalah dengan kerjasama internasional dalam
pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dengan mengedepankan I
prinsip resiprokal atau timbal balik dan itikad baik sesuai dengan ketentuan
hukum internasional yang berlaku dalam kerjasama internasional serta
74
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pemba/akan Liar-2008
menggiatkan peran serta masyarakat. Dalam rangka meningkatkan peran
serta masyarakat dan seluruh pihak yang berjasa, maka upaya pencegahan
dan pemberantasan pembalakan liar juga menganut sistem reward dengan
memberikan penghargaan atau insentif.
2. Bentuk kelembagaan yang tepat sebagai penanggungjawab upaya
pembalakan liar secara nasional yakni suatu bentuk koordinasi antar
lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan yang tegas dan jelas
baik dalam melaksanakan fungsinya sebagai kelembagaan yang
mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar
maupun dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum yakni melakukan
penyelidikan dan penyidikan. Kelembagaan tersebut di bentuk di tingkat
pusat dan di tingkat daerah sehingga dalam penanganan illegal logging
dapat dilakukan secara terpadu dan terintegrasi.
3. Pengaturan sanksi yang dilakukan dalam pemberantasan illegal logging
menggunakan bentuk sanksi minimal dan maksimal dan dengan konsep
penjatuhan sanksi ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap
pelaku kejahatan pembalakan liar. Selain itu dalam pengaturan dan
disparitas sanksi juga didasarkan pada kriteria atau standar penghukuman,
akibat tindakan bahkan keterlibatan unsur pejabat. Selain penjatuhan
sanksi pidana, dikenakan juga uang pengganti, dan apabila tidak terpenuhi,
maka terdakwa dapat dikenakan hukuman badan. Sedangkan untuk pelaku
badan hukum atau korporasi yang melakukan pembalakan liar dan
mengakibatkan kerusakan lingkungan dikenai pula sanksi administrative
seperti paksaan pemerintah,, uang paksa dan pencabutan izin.
B. Saran
Naskah akademik ini memandang perlu dibentuknya Undang-Undang
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan liar dimana dalam
pembentukan dan penyusunannya sebaiknya memperhatikan konsep
pembuatan hukum yang efektif.
75
,Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Uar-2008
-
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Ahmad, Rival Gulam, dkk. Manual Perancangan Peraturan Untuk Transformasi Sosial, Jakarta: PSHK, 2005.
Ahmed, Abdullah An Nairn. Dekonstruksi Syari'ah. Yogyakarta: LkiS dan Pusta Pelajar, 1990.
Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembang Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Legislatif dalatn Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Semarang: CV Ananta, 1994.
Dworkin, Ronald, Legal Research, (Daedalus: Spring), 1973
Concklin, John E. The Impact of Crime. New York: Macmillan Publishing Co. Inc., 1975.
Erawati, Elly, dkk. Keterampilan Perancangan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
Evans, William dalam Lawrence M Friedman, Law and Society (Prentile-Hall,lnc, Engleewood,Cliffs, New Jersey,07632,tanpa tahun
D. Prasetyo, Illegal Logging, Suatu Malpraktek Bidang Kehutanan, makalah pada Semiloka lnisiatif Daerah dalam Penanggulangan Illegal Logging, 9 Januari 2003
Hanidjo Soemitro, Ronny. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
Hardjasumantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan,Cet. Ke-17, edisi ke-7,Gadjah Mada University Press-Yogyakarta, 1999
Hidayati, Rahmi, et al. Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutana Banten: Wana Aksara, 2006.
Kadish, Sanford H. (Ed). Encyclopaedia of Crime and Justice, Volume 1. London: Collier Macmillan Publication Co, 1990.
76
. Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan liar-2008
Kartodihardjo, Harijadi, dkk, Structural Problems in Implementing New Foresty Polices, in Resosudarmo, Isa Aju Pradnja and Carol J. Pierce Golfer (eds) Which Way Forward: Forest, People and Public Policy, CIFOR. Bogar: 2003.
Kartodihardjo, Harijadi, dkk. Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jakarta: Suara Bebas. 2005
M. Colchester, et.al, Justice in the Forest: Rural Livelihoods and Forest Law Enforcement, Bogor, Indonesia: Center for lnternasional Forestry Research. 2006.
Marmosodjono, Sukarton. Penegakan Hukum Di Negara Pancasi/a. Jakarta; Pustaka Karting. 1989
Muladi dan Barda Nawawi. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 1992.
Murtijo,, Agung Nugraha, Antropologi Kehutanan, Wana Aksara, Banten, Indonesia, 2005.
Peters, A.AG. dan Koesriani Siswosoebroto. Hukum dan Perkembangan Sosial- Buku teks Sosiologi Hukum Buku Ill .. Jakarta: Sinar Harapan, 1990.
Priyono dan Pranarka (penyunting), Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan lmplementasi, Jakarta: CSIS, 1996,
Purnianti dan Moh. Kemal Darmawan. Mazhab Dan Penggolongan Teori Da/ar Kriminologi, Bandung Citra Aditya Bakti, 1994.
Saleh, Roeslan. Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan Dan Kesalahan Dalar Hukum Pidana. Yakarta: Aksara Baru, 1985.
Salim, HS. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
Sholehuddin, M. Sistem Sanksi Dalatn Hukum Pidana - Ide Dasar Double Trac, System Dan lmplementasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Rajawali Pers, 1983
Soeprapto, Maria Farida lndrati. I/mu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
Suarga, Riza, dkk. Mencari Supremasi Hukum. cetakan kedua. Jakarta: Arivco Press. 2004
77
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
Suarga, Riza. Pemberantasan Illegal Logging. Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global. Banten: Wana Aksara, 2005.
Sukardi. Penebangan Pohon di Dalam Hutan Secara Tidak Sah Dalam Prespektil Po/itik Hukum Pidana (Kasus Papua). Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2005.
Makalah
Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan,"Pemberantasan Illegal logging Membangkitkan Ekonomi Indonesia," Makalah disampaikan pada Seminar Upaya Mengatasi //legal logging Di Indonesia, Jakarta 3 April 2006.
Gede, Ngurah. Apakah Perlu RUU Khusus untuk Memberantas Illegal Logging: Suatu Kajian. Maka/ah untuk Tim Kerja Perancangan RUU Penebangan Pohon di Dalam Hutan Secara Tidak Sah. Jakarta, 2006.
Kartodihardjo, Harijadi. Kajian Aspek social-Ekonomi dan lnstitusi Mengatasi Illegal logging di Indonesia. Makalah disampaikan pada Seminar Upaya Mengatasi Illegal logging di Indonesia. Jakarta, 3 April 2006.
Laode, M. Kamaludin., 2005. Kerugian Negara yang Oitimbulkan Akibat Illegal Logging dan Antisipasi Oitinjau dari Aspek Ekonomi dan Ekologi, Makalah disampaikan pada acara Seminar Nasional "Illegal Logging, Permasalahan dan Penanggulangannya di Indonesia, Tinjauan Hukum, Ekonomi, dan Manajemen, diselenggarakan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 16 Mei 2005
Manan, Bagir. Politik Perundang-undangan. Makalah disampaikan pada Penataran Dasen Fakultas Hukum/Sekolah Tinggi Hukum PTS se Indonesia, diselenggarakan oleh Dit Gutiswa Ditjen Dikti di Cisarua. Bogar, Tanggal 26 September s/d Oktober 1993.
Padhista, Chai, "Theorical,Terminological, and Philosophical Issue in Qualitative Research", dalam Attig.et.al, A Field Manusal an Selected Qualitative Research Methods, (Thailand: Institute for Population and Social Research, Mahidol University) 1991
Rianto, Bibit S. Kata Sambutan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Makalah disampaikan pada Seminar Illegal logging, Permasalahan dan Penangannya di Indonesia. Jakarta: 16 Mei 2005.
78
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
Rizal, Jufrina. Sosiologi Perundang-undangan. Makalah disampaikan pada Pendidl:kan dan Latihan Tenaga Teknis Perundang-undangan Sekretariat Jenderal DPR
1
, RI .. Jakarta: Tahun 2003.
Saleh, Roeslan. Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi. Makalah disampaikan padaSeminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia di Fakultas Hukum Ull. Yogyakarta: 15 Juli 1993.
Suparna, Nana. Illegal Logging Dari Sisi Sistem Pengelolaan Hutan, Makalah disampaikan pada seminar Nasional mengenai Illegal Logging, Permasalahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia Didekati dari aspek Hukum, Ekondmi, d'an Manajemen, Jakarta: 16 Mei 2005.
Sist, Plinio, Robert Fimbel, Douglas Sheil, Robert Nasi, and Marie-Helene Chevalliier. "Towards Sustainable Management of Mixed Dipterocarp Forests of South-east Asia: Moving beyond Minimum Diameter Cutting Limits." Environmental Conservation 30 (4): 2003.
Sist, Plinio,Timothy Nolan, Jean-Guy Bertault, and Dennis Dykstra. "Harvest,ing Intensity versus Sustainability in Indonesia." In Forest Ecology and Management, 1998.
Tabah, Anton. Mengurai Anatomi Illegal Logging Dan Deforestasi Di lndone~ia. Makalah pada Seminar Nasional di Manggala Wana Bhakti. Jakarta: 16 Mei 2005.
Peraturan Perundang-Undangan
Anonimous. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
____ . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Vang.
____ . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. ·
____ . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
____ . Undang-Undang Nomor41Tahun1999 tentang Kehutanan. 79
.Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan liar-2008
____ . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
____ . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
____ . Undang-Undang tentang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
____ . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria.
____ . Undang-Undang No.11Tahun1967 tentang Pertambangan Umum.
____ . Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
____ . Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
____ . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
____ . Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan.
____ . lnstruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara I/legal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
80
Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar-2008
,.....