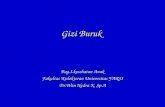Gizi Buruk
-
Upload
wazny-ezen-taeminjun-sidjmelankolist -
Category
Documents
-
view
81 -
download
0
Transcript of Gizi Buruk
Haruskah kita membiarkan mereka tetap seperti ini?Masalah gizi seperti ini masih saja terjadi padahal kita adalah negara yang katanya gemah ripah loh jinawi. Ada apakah sebenarnya dengan nergeriku yang kaya ini? February 5, 2009 Posted by anwarsasake73 | Uncategorized | Leave a Comment
PPH sebagai indikator keragaman tingkat konsumsi masyarakat1. Berdasarkan hasil Susenas 2007 mengenai informasi pangan yang dikonsumsi penduduk Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut : a. Tingkat ketersediaan dan kecukupan pangan di Kabupaten Lombok Timur berupa ketersediaan energi rata-rata sebesar 3.077 kkal/kap/hari, dan ketersediaan protein rata-rata sebesar 93,80 gram/kap/hari berarti melebihi dari Angka Ketersediaan Nasional yang dianjurkan menurut WKPG 2004 sebesar 2200 kkal/kap/hari dan 57 gram protein/kap/hari. Data ini menunjukkan bahwa Ketersediaan pangan di Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB telah mencukupi untuk kebutuhan konsumsi masyarakatnya sesuai kebutuhan yang dianjurkan baik untuk kecukupan energi maupun protein. Walaupun demikian ketersedian dan kecukupan bahan pangan di Kabupaten Lombok Timur Propinsi NTB ini masih di dominasi oleh sumbangan bahan makanan nabati, baik untuk ketersediaan energi maupun protein. b. Tingkat keragaman pangan di Kabupaten Lombok Timur masih didominasi oleh bahan makanan bersumber nabati , dimana sumbangannya sebesar 2,992,70 kalori atau 97,24 % dan sisanya 84,88 gram atau 2,76 % bersumber dari pangan hewani. Kontributor kalori terbesar bersumber dari kelompok bahan makanan padi-padian sebesar 2.166,18 kkal/kap/hari (70,38 9 %), buah/biji berminyak 295,76 kkal/kap/hari (9,61 %), minyak dan lemak sebesar 251,42 kkal/kap/hari (8,17%), buah-buahan sebesar 84,07 kkal/kap/hari (2,73 %), makanan berpati sebesar 74,67 kkal/kap/hari (2,43 %), gula sebesar 72,94 kkal/kap/hari (2,37 %), sayur-sayuran sebesar 50,10 kkal/kap/hari(1,63 %), ikan sebesar 40,25 kkal/kap/hari (1,31 %), daging sebesar 36,83 kkal/kap/hari (1,20 %), telur sebesar 5,37 kkal/kap/hari (0,17 %) dan susu tidak tersedia.
c.
Konsumsi energi penduduk kabupaten Lombok Timur adalah 2.045 kkal/kap/hari berarti lebih tinggi dari standar kebutuhan pangan nasional (2.000 kkal/kap/hari). Jika dilihat konsumsi kelompok pangan padi-padian terlihat lebih tinggi yaitu 1.530 kkal/kap/hari atau 153 % lebih tinggi dari konsumsi pangan nasional (1.000 kkal/kap/hari), namun konsumsi kelompok pangan lainnya masih lebih rendah dari standar kebutuhan konsumsi pangan nasional. Hal ini disebabkan karena produksi padi di Kabupaten Lombok Timur cukup bagus bahkan menjadi lumbung padi wilayah sekitarnya, sedangkan bahan pangan yang lain harganya masih relatif tinggi.
d.
Pendapatan daerah di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp. 3.800,9 Milyar dan PDRB Per Kapita Rp.3.608.386. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Lombok Timur pasca krisis secara faktual cukup berhasil, dimana volume dan kapasitas nilai tambah yang dicipatakan meningkat, laju pertumbuhan ekonomis dinamis dan stabil. Dengan stabilnya ekonomi dan
peningkatan PDRB dan PDRB per Kapita maka diharapkan pemenuhan konsumsi masyarakat tidak akan mengalami masalah. e. Share sektor pertanian pada PDRB Kabupaten Lombok Timur sebesar 38 % menunjukkan pentingnya sektor pertanian dalam menunjang perekonomian masyarakat. Berdasarkan data produksi tahun 2007, menunjukkan rata-rata produksi beras sebesar 156.096 ton, jagung sebesar 30.905 ton, kedelai sebesar 1.131 ton. Dengan produksi beras tersebut untuk kebutuhan penduduk sebanyak 1.067.673 jiwa dan FBS/kapita 122 kg maka konsumsi total lokal beras sebanyak 130.256 ton sehingga terjadi surflus beras sebesar 25.839 ton. Sedangkan dari produksi ternak seperti sapi masih cukup dimana produksi sapi 64.947 ekor, kerbau 5.745 ekor, kambing 61.091 ekor , domba 11.898 ekor, kuda 6.658 ekor dan unggas 1.772.435 ekor serta produksi ikan sebesar 15.995,78 ton. f. Dari data-data tersebut di atas maka untuk tahun 2009 jika kondisi seperti ini terus terjadi dan tidak ada kegagalan produksi dan faktor-faktor yang lain normal maka tidak akan terjadi perpindahan konsumsi pangan pada masyarakat. February 5, 2009 Posted by anwarsasake73 | Uncategorized | Leave a Comment
REFORMASI BIDANG PANGAN DAN GIZI
1. Penerapan Konsep SKPG Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah. Dengan adanya undang-undang Otonomi daerah, maka setiap daerah diberikan wewenang untuk mengatur wilayahnya sendiri, sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah. SKPG sebagai sistem informasi kondisi pangan dan gizi di suatu daerah sudah selayaknya mendapat perhatian yang lebih, karena masalah pangan dan gizi disamping merupakan masalah pokok masyarakat juga dapat berdampak pada masalah-masalah sosial yang lain. Dengan adanya PP no.41 tahun 2007, maka di daerah harus ada badan yang menangani ketahanan pangan yaitu dalam bentuk Badan Ketahanan Pangan Daerah. Agar pelaksanaan SKPG berjalan dengan baik pada setiap kondisi baik normal maupun krisis maka yang menjadi leading sector kegiatan adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah dengan anggota dari Dinas-dinas teknis terkait seperti Dinas Pertanian, Peternakan, perikanan , Kesehatan, Bulog, Deperindag dan lain sebagainya. Tugas dari Badan ini antara lain : Mengkoordinasikan informasi menyangkut masalah pangan dan gizi secara kontinyu dan teratur; Menyediakan dana kegiatan baik yang bersifat rutin maupun insidentil; Bersama Tim Melakukan analisa data secara berkala untuk kebutuhan kebijakan pangan dan gizi daerah; Bersama Tim melakukan advokasi ke Executif (Bupati, Bappeda, Panggar Executiv) dan Legislatif (DPRD II) untuk mendapatkan perhatikan dari Pemerintah baik berupa kebijakan maupun berupa anggaran. Melaporkan secara berkala perkembangan kondisi pangan dan gizi daerah. Menyangkut perimbangan peran : Dalam pelaksanaan SKPG, Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri tetapi harus melibatkan peran pihak lain seperti swasta dan LSM, tetapi yang lebih penting adalah adanya pembagian peran yang sesuai dengan bidang masing-masing agar tidak terjadinya peran yang tumpang tindih. Untuk itu perlu diberikan peran masing-masing seperti : a. Pemerintah : - Sebagai pembuat kebijakan dalam bidang pangan dan gizi ; - Sebagai regulator atau pembuat peraturan dalam bidang pangan dan gizi yang menyangkut sistem produksi, pengolahan dan perdagangan pangan di suatu wilayah ; - Menjaga ketersediaan dan keamanan pangan di suatu wilayah. b. Swasta - Membantu pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan di suatu wilayah; - Menjaga kestabilan harga bahan pangan agar dapat terjangkau oleh masyarakat; - Tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan keamanan dan kestabilan bahan pangan terganggu seperti penimbunan dan lain sebagainya. c.LSM/NGO - Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pangan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta; - Memberikan masukan kepada pemerintah tentang hal-hal yang terjadi di lapangan menyangkut ketersediaan pangan; - Membantu pemerintah dalam mendidik masyarakat agar dapat memilih makanan yang tepat sehingga tidak menimbulkan ketergantungan yang tinggi pada salah satu bahan makanan; - Membantu pemerintah pada saat krisis serperti terjadi KLB dan lain sebagainya. 2. Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan krisis pangan dan gizi, informasi-informasi yang dibutuhkan meliputi ;
a. Informasi Pangan yang meliputi : - Luas lahan produksi, baik padi, palawija, perikanan darat, perikanan laut, hewan ternak berupa sapi, kambing dan domba, unggas dan lain sebaginya. - Luas kerusakan lahan dan tempat terjadinya kerusakan lahan; - Data ini dikumpulkan dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan b. Informasi Status gizi seperti : - Prosentase Gizi Kurang dan Gizi Buruk - Kecenderungan prosentase Balita Bawah Garis Merah (BGM). - Kecenderungan N/D berdasarkan hasil pemantauan pertumbuhan di Posyandu. - Jumlah balita yang mengalami gizi kurang dan gizi buruk; - Data ini dikumpulkan dari Dinas Kesehatan. c. Informasi jumlah keluarga miskin baik dari BPS maupun dari Kantor KB/BKKBN; Penerapannya di Kab.Lombok Timur : o Berdasarkan pengalaman kami ( kebetulan sebagai anggota Tim SKPG Kab. Lombok Timur) dan wawancara dengan Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur maka selama ini Tim SKPG di Kabupaten Lombok Timur masih berjalan dengan cukup baik , hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya pertemuan secara berkala Tim SKPG Kabupaten untuk membahas kondisi pangan dan gizi yang dihadapi . o Informasi produksi pangan akan dibawakan oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan untuk mengetahui jumlah produksi pangan, baik berupa hasil pertanian, peternakan dan perikanan yang ada, juga dibahas mengenai jumlah luas lahan dan keruasakan lahan yang terjadi serta perkiraan produksi hasil pertanian berdadaskan luas lahan yang di tanam. o Dinas Kesehatan akan menyampaikan hasil pemantauan status gizi (PSG) terutama prosentase gizi buruk dan gizi kurang, hasil pemantauan Pertumbuhan terutama wilayah dengan BGM tinggi dan N/D rendah. Semua data yang dikumpulkan akan diolah untuk menentukan wilayah rawan pangan dan gizi atau rawan gizi saja, yaitu jika suatu wilayah tidak mengalami permasalahan pangan tetapi hanya masalah gizi saja (Jika gizi kurang dan gizi buruk > 15 % BB/U). o Pada daerah daerah rawan dan waktu waktu tertentu Tim SKPG juga akan melakukan kunjungan sampai tingkat RT untuk mengetahui ketersediaan pangan tingkat Rumah Tangga. Pada kesempatan ini juga dilakukan untuk mengtahui adanya perubahan pola konsumsi pangan tingkat Rumah Tangga. o Swasta dan LSM juga sudah menunjukkan kiprahnya, terutama begitu propinsi NTB termasuk Kabupaten Lombok Timur ditetapkan sebagai daerah KLB gizi buruk, dimana mereka terlibat membantu penanggulangan kasus gizi buruk. 3. Bagaimana saudara bisa melihat akan terjadi gangguan ketersediaan pangan di daerah dilihat dari : a. Informasi tentang riwayat masalah konsumsi; - Waktu/ bulan biasanya terjadinya gangguan persediaan pangan. Dimana biasanya pada bulan tertentu seperti september- oktober yang merupakan puncak musim kemarau, dimana masyarakat di Kabupaten Lombok Timur biasanya menanam tembakau tetapi hasilnya belum bisa dinikmati, sedangkan persediaan bahan pangan sudah berkurang. Jika pada bulan-bulan ini kita perhatikan sudah terjadi perubahan pola konsumsi yang umumnya adalah penurunan frekuensi makan menjadi kurang dari 3 kali maka itu merupakan tanda akan terjadinya gangguan ketersediaan pangan terutama tingkat rumah tangga.
- ada beberapa kecamatan rawan pinggir pantai, masalah cuaca merupakan masalah yang menjadi indikator yaitu jika terjadi musim barat dan musim timur dimana pada saat itu para nelayan tidak berani melaut, yang berdampak pada perubahan pola konsumsi. b. Indikator peramalan - Jika terjadi gagal panen, atau terjadi kerusakan lahan pertanian akibat hama, maka dapat diramalkan pada wilayah itu akan terjadi gangguan persediaan pangan ; - Jika terjadi bencana alam seperti banjir, kekeringan dan gempa bumi, maka perlu diperhatikan daerah tersebut tentang ketersedian bahan pangannya. Jika tidak tempat tersebut diramalkan akan terjadi rawan pangan. - Penurunan luas lahan pertanian dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pada periode yang sama, luas kerusakan lahan lebih besar, hasil panen per hektar menurun, popylasi ternak, hasil tangkapan dan panen periakanan darat /tambak menurun. - Ketersediaan pangan pada tingkat distribusi dan konsumsi terus menurun, diikuti terjadinya kenaikan pada tingkat distribusi. - Data status gizi balita berupa KEP meningkat; - Perubahan iklim dan penurunan curah hujan yang tidak mendukung pertanian yang baik. c. Indikator pengamatan. - Jika akan terjadi gangguan ketersediaan pangan biasanya dapat dilihat meningkatnya kasus pencurian terutama pencurian ternak di suatu wilayah, - Meningkatnya angka perceraian - Banyaknya orang yang menggadaikan barang barang ke kantor pengadaian atau menjual barang-barang rumah tangga ke pasar loak. - Banyaknya para pencari kerja ke luar daerah, terutama semakin banyak yang berminat menjadi TKI/TKW ke Malaysia dan Arab Saudi. 4. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam koordinasi pelaksanaan SKPG di wilayah Kabupaten Lombok Timur antara lain : a. Sulitnya menyatukan jadwal antar masing-masing sektor. Disepakati diadakan pertemuan secara reguler setiap 3 bulan sekali atau lebih sesuai kebutuhan. Namun pelaksanaannya sering tidak dilaksanakan dengan berbagai alasan seperti kesibukan masing-masing sektor dan tidak adanya dana kegiatan. b. Terjadinya ego sektoral dan ego program Masing-masing sektor sering membuat perencanaan kegiatan penanggulangan masalah pangan dan gizi secara sendiri-sendiri. Hal ini menyebabkan kegiatan penanggulangan masalah pangan dan gizi tidak dapat dilakukan secara komprehensif tetapi secara sektoral. Alternatif Solusi Pemecahan masalahnya adalah : a. Dengan adanya otonomi daerah maka perlu adanya penguatan kelembagaan SKPG di Daerah, yaitu dengan memberdayakan Kantor Ketahanan Pangan Daerah sebagai leading sektor dalam SKPG. Dengan adanya leading sektor yang jelas maka masalah alokasi anggaran dan koordinasi bisa direncanakan dengan jelas. b. Dalam perencanaan kegiatan pangan dan gizi setiap sektor harus melakukan koordinasi tentang daerah yang akan mendapatkan kegiatan berdasarkan hasil analisa data SKPG sebeleumnya. Dengan hal ini diharapkan tidak terjadi kesimpang siuran pelaksanaan kegiatan. c. Tim SKPG harus lebih sering melakukan advokasi kepada para pengambil kebijakan seperti Bupati, DPRD dan Panggar Eksekutiv agar masing-masing pengambil kebijakan
tersebut betul-betul paham tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi secara komprehensif , Oleh karena itu maka diperlukan anggaran yang sesuai yang menyatu pada peran masing-masing sektor. d. Perlu adanya upaya memperkuat pelaksanaan SKPG dengan merangkul lebih erat pihak swasta dan LSM/NGO, media massa, tokoh agama dan tokoh masyarakat agar masingmasing merasa mempunyai perananan dalam pelaksanaan SKPG. 5. Peranan Saya dan Instansi ( Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kab. Lombok Timur) dalam pelaksanaan kegiatan SKPG antara lain : a. Dalam Keadaan Normal : - Menyediakan data status gizi balita per kecamatan, menyangkut prosentase KEP, Balita BGM dan N/D. - Melakukan upaya perbaikan gizi masyarakat melalui Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) baik di Posyandu maupun di luar Posyandu; - Membina Keluarga menjadi Keluarga Mandiri Sadar Gizi (Kadarzi); - Memberikan PMT Penyuluhan di Posyandu dan PMT Pemulihan pada kasus gizi buruk; - Memberikan MP-ASI kepada Balita 6-23 bulan dari keluarga miskin untuk menjaga dan meningkatkan status gizinya. - Memberikan talkshow masalah gizi di TV Lokal dan mengimformasikan tentang pemilihan bahan makanan yang sehat, bergizi dan murah. b. Dalam Keadaan Krisis : - Menyediakan informasi tentang besaran masalah kasus gizi buruk dan gizi kurang serta lokasi-lokasi penyebarannya; - Jika terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor kita memberikan fokus perhatian lebih kepada kelompok rawan seperti bayi, balita dan ibu hamil dengan menyediakan makanan tambahan bagi mereka, bisa berupa bubur dan biskuit untuk memenuhi kebutuhan gizinya selama masa krisis; - Pada kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk maka kami sebagai anggota Tim Operasi Sadar Gizi (OSG) bersama-sama dengan tim melakukan upaya komprehensif dalam penanganan masalah gizi buruk, dimana dinas kesehatan beserta jajarannya dan RS bertanggung jawab secara medis terhadap penanganan masalah gizi buruk tersebut dan instansi lain serta swasta bertanggungjawab terhadap hal-hal lain di luar kesehatan seperti ketersediaan bahan pangan, penyuluhan dari sisi agama, pendampingan oleh LSM dan lain sebagainya. 6. a. Perubahan pola kosumsi golongan miskin akibat perubahan sejumlah parameter pentng bagi pengambil keputusan berubah; Golongan miskin merupakan kelompok yang paling cepat terkena dampak dari perubahan kebijakan, namun biasanya pada kondisi ini mereka cenderung akan bertindak rasional dalam pemilihan bahan makanan yaitu dengan melakukan substitusi bahan pangan ke yang lebih rendah statusnya misalnya dari beras ke jagung atau beras jagung. Demikian pula dengan pola konsumsi dimana mereka akan mengurangi frekuensi makan mereka. b. Perubahan konsumsi energi dan protein akibat : Perubahan Pendapatan : Jika terjadi perubahan pendapatan dalam arti terjadi peningkatan pendapatan maka akan terjadi peningkatan konsumsi makanan sumber protein terutama sumber protein hewani sedangkan makanan sumber energi dari karbohidrat akan menurun. Begitu juga sebaliknya jika terjadi penurunan pendapatan maka konsumsi sumber energi dari karbohidrat cenderung
meningkat sedangkan sumber energi dari lemak dan protein khususnya protein hewani akan menurun. Perubahan Harga : Bila terjadi perubahan harga pangan maka konsumsi makanan sumber protein pada golongan miskin khususnya protein hewani akan mengalami penurunan, sehingga pemenuhan kebutuhan protein akan beralih ke sumber protein nabati. Pemenuhan kebutuhan energi akan dipenuhi dari makanan sumber karbohidrat. Jika kenaikan harga terus terjadi maka akan terjadi upaya mencari sumber bahan makanan baru yang terjangkau walaupun lebih rendah statusnya dari sebelumnya. Jumlah Anggota Keluarga : Terjadinya perubahan jumlah anggota keluarga dalam hal ini bila jumlah anggota keluarga bertambah sedangkan faktor yang lain tidak berubah seperti pendapatan dsbnya, maka akan terjadi penurunan pemenuhan kebutuhan energi dan protein anggota keluarga terutama kebutuhan protein hewani. Hal ini terjadi akibat semakin banyaknya anggota keluarga yang harus mendapatkan bagian. Tempat Tinggal : Perubahan tempat tinggal dapat mempengaruhi konsumsi energi dan protein. Jika keluarga miskin pindah dari desa ke kota, maka konsumsi energi akan bertumpu pada satu jenis bahan pangan sumber karbohidrat misalnya beras, hal ini akan berbeda di desa dimana mereka dapat menggunakan sumber energi dari karbohidrat yang bermacam-macam. Konsumsi protein terutama hewani akan mengalami penurunan karena hargaya yang relatif mahal. Tapi pada keluarga yang kaya pindah ke kota maka akan terjadi peningkatan makanan sumber lemak dan protein hewani karena adanya kemudahan akses mendapatkannya. Perubahan status kesehatan : Perubahan status kesehatan dapat mempengaruhi konsumsi energi dan protein seseorang, dimana jika terjadi penurunan status kesehatan akibat suatu penyakit maka akan terjadi pembatasan pada konsumsinya baik energi maupun protein misalnya jika terjadi obesitas atau Diabetes Melitus.Namun hal ini sulit dilakukan pada golongan miskin karena terbatasnya sumber daya yang ada pada mereka. Oleh karena itu perubahan status kesehatan biasanya akan menurunkan konsumsi energi dan protein golongan miskin. Perubahan Musim : Perubahan musim dapat mempengaruhi konsumsi energi dan protein pada golongan miskin. Jika terjadi perubahan musim dimana bahan makanan sumber energi dan protein menjadi terbatas jumlahnya maka akan menyebabkan harga menjadi naik, yang berdampak pada terbatasnya kemampun golongan miskin untuk membelinya. Ini sangat nyata terlihat pada konsumsi protein, misalnya pada musim barat dimana nelayan tidak dapat melaut maka orang akan membeli ayam atau daging sebagai pengganti ikan, ini menjadi sulit bagi golongan miskin. Oleh karena itu perubahan musim dapat menyebabkan menurunnya konsumsi energi dan terutama protein pada golongan miskin Kebijakan Beras Miskin : Kebijakan beras miskin merupakan salah satu kebijakan yang dapat membantu golongan miskin memenuhi kebutuhan konsumsinya terutama kebutuhan energinya. Dengan kebijakan ini diharapkan setiap keluarga miskin minimal dapat memenuhi kebutuhan energi setiap
anggota keluarganya. Hal ini juga dapat membantu keluarga miskin untuk mengalokasikan sumber daya yang ada pada mereka untuk konsumsi yang lain seperti memenuhi kebutuhan protein atau kebutuhan lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ini juga dapat membantu masyarakat tidak mengalami masalah yang lebih parah lagi apabila terjadi perubahan pada hal-hal lain , namun walaupun demikian pelaksanaan di lapangan perlu ditertibkan antara lain : - Harus dilakukan klarifikasi tentang golongan yang berhak mendapatkan beras msikin tersebut; - Jumlahnya harus disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga miskin tidak dihitung per KK tetapi per individu; - Tidak terjadi korupsi dan kolusi dalam pemberian beras miskin tersebut. February 5, 2009 Posted by anwarsasake73 | Uncategorized | Leave a Commenthttp://anwarsasake73.wordpress.com/
Siapa tak kenal Indonesia, negeri yang kesohor sebagai sumber rempah-rempah dan berbagai komoditi perkebunan. Di sepanjang gugusan pulaunya terkandung beraneka ragam bahan tambang. Hutan membentang indah, memahkotainya julukan zamrud khatulistiwa. Di dalam birunya laut, tersimpan potensi sangat besar yang menyanyikan janji kesejahteraan. Jangan tanya tentang indahnya gunung dan pantai. Sungguh tiada tara. Tetapi negeri kita tidak hanya terkenal dengan berbagai kebanggaan di atas. Negeri ini bukan sekadar surga bagi investor pertambangan dan wisatawan manca negara, tetapi juga bagi beraneka ragam penyakit dan penderitaan. Diare dan Muntaber Di seluruh dunia, setiap tahun 1,6 juta anak meninggal dunia karena diare. Jadi setiap 30 detik, satu anak meninggal dunia karena sakit perut ini. Sementara di Indonesia, diare adalah penyebab kematian balita terbesar kedua setelah manultrisi (gizi buruk). Rata-rata setiap tahunnya 100.000 anak mati karena diare dan dari 1.000 bayi yang lahir, 50 di antaranya meninggal dunia karena diare (Kompas, 1 Feburari 2007). Penyakit ini bertalian erat dengan akses masyarakat terhadap sanitasi yang baik. Sanitasi sangat berkaitan dengan akses terhadap air bersih. Karena itu tidak heran jika pada tahun 2005, Nusa Tenggara Timur yang terkenal dengan keterbatasan akses rakyat terhadap air bersih, mencatat kejadian luar biasa (KLB) diare paling banyak, dengan jumlah penderita mencapai 2194 orang, dan 28 di antaranya meninggal dunia. Prestasi negatif ini diikuti Provinsi Banten dan Papua. Namun tingkat kematian penderita yang paling tinggi terjadi di Sulawesi Tengah: dari 69 penderita di tahun 2005, sebanyak 13 di antaranya meninggal dunia (Kompas Online, 26 Juni 2006).
Prestasi serupa kembali dicatat Provinsi NTT pada tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 2006, terdapat lima kabupaten dengan kasus KLB gizi buruk, yang selain kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), masing-masing mencatat kematian 2 sampai 5 orang anak. Sementara di Kabupaten TTS, 25 sepanjang Agustus 2006-12 Oktober 2006, 28 dari 672 orang anak balita penderita diare meninggal (Kompas, 10 Okober 2006 dan 12 Oktober 2006). Pada tahun 2007, untuk Kota Kupang saja tercatat sebanyak 544 anak balita penderita diare. Dari jumlah tersebut, 12 orang di antaranya meninggal dunia. Demikian pula halnya di Papua. Sepanjang quartal pertama tahun 2006, terdapat 2.145 penderita diare di Kabupaten Jayawiyaja, 151 orang di antaranya meninggal. Di Kabupaten Yahukimo tercatat 317 kasus dan 30 orang di antaranya meninggal (www.infopapua.com). Di Sulawesi Tengah, sepanjang Juli hingga Agustus 2007, 5 orang anak usia 6-10 tahun dan 11 orang usia 16-62 tahun di Desa Lombok Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong meninggal dunia akibat diare (Radar Sulteng 23-24 Juli 2007). Di Kota Palu, jumlah penderita diare pada tahun 2007 mencapai 4109 orang. Malaria, Demam Berdarah dan Kaki Gajah Di dunia tercatat rata-rata 50 juta kasus demam berdarah (demam berdarah dengue --DBD) setiap tahunnya. Di Indonesia, meski demam berdarah telah dikenal sejak 40 tahun lampau, hingga kini penyakit ini masih menjadi momok tahunan. Pada 1998, jumlah penderita DBD yang tercatat mencapai 71.776 orang dengan kematian 2.441 jiwa (CFR 3,4%). Di tahun 1999 jumlah penderita tercatat turun menjadi 21.134 orang, dan di tahun-tahun selanjutnya terus meningkat: 2000 (33.443 orang), 2001 (45.904 orang), 2002 (40.377) dan 2003 (50.131). Di tahun 2004, hanya dalam 6 bulan, demam berdarah memyerang 53.321 orang dan membunuh 669 orang (Eko Prasetyo, Orang Miskin Dilarang Sakit, Resist Book, 2004). Sementara di tahun 2005, hanya dalam 10 bulan, kasus DBD di 33 provinsi mencapai 50.196 kasus, dengan 701 di antaranya meninggal (case fatality rate 1,4 persen) (Koran Tempo, November 2006). Seperti halnya demam berdarah, secara global, malaria juga menjadi masalah kesehatan paling besar dengan sekitar satu miliar kasus penularan/demam yang menyebabkan kematian satu juta hingga tiga juta jiwa per tahun atau satu kematian setiap 30 detik. Malaria utamanya tersebar di kawasan sekitar khatulistiwa, di negara-negara Amerika Latin, Afrika sub-Sahara, Asia Selatan, sebagian Asia Timur (utamanya China), dan Asia Tenggara. Sebanyak 45 persen dari kasus malaria global ada di Asia Tenggara (500 juta kasus per tahun).
Di Indonesia rata-rata tak kurang dari 15 juta penduduk diobati untuk demam malaria setiap tahun. Pada tahun 2004, prevalensi malaria di Indonesia adalah 50 per 1000 penduduk, sementara pada tahun 2007, sebanyak 107.785.000 orang atau 49,6 persen penduduk Indonesia di 310 kabupaten/kota berisiko tertular malaria. Pada tahun 2006 dan 2007 malaria dinyatakan sebagai kejadian luar biasa (KLB). Di tahun tersebut, terjadi peningkatan kasus malaria di 8 kabupaten di 8 provinsi, yang meliputi 20.331 penduduk di 12 desa dengan kesakitan sejumlah 1.051 orang dan kematian 23 orang--Case fatality rate sebesar 2,19% (Kompas Online, 26 April 2007). Daerah-daerah di kawasan timur Indonesia seperti NTB, NTT, Papua, Sulawesi, dan Kalimantan berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Untuk Papua, prevalensinya mencapai 16 persen dari seluruh penduduk, tiga kali lipat rata-rata nasional (Kompas, 7 Nov 2007). Sementara di Kota Palu, Sulteng, penderita DBD di tahun 2007 tercatat sebanyak 916 orang, meningkat signifikan dari angka tahun 2006 yang sebanyak 334 kasus. Sementara di NTT, pada tahun 2007 sebanyak 535.591 penduduk menderita malaria. Kasus terbanyak di Kabupaten Sumba (94.986 pasien), Sikka (87.623 pasien) dan Ende (75.709 orang). Kabupaten lain antara 4.000 sampai 36.000 penderita. Penyakit endemik lain yang juga ditularkan nyamuk adalah kaki gajah (filariarsis). Kaki gajah dipetakan masuk Indonesia sejak 1927 dan mulai mendapat penanganan tahun 1972. Namun, seperti halnya demam berdarah dan malaria, masih terdapat jumlah yang sangat besar dari penduduk Indonesia yang menderita kaki gajah. Pada tahun 2002 diperkirakan sekitar 10 juta penduduk Indonesia menderita filariasis (kaki gajah). Sebanyak 6500 orang perderita kronis, terutama yang tinggal di desa-desa. Di Kabupaten Alor, NTT dinas kesehatan memperkirakan 114 ribu jiwa dari 164 ribu pendduk di 172 desa menderita kaki gajah (Eko Prasetyo,2004) Tuberkolosis (TB) Ancaman lain bagi rakyat Indonesia adalah tuberkolosis (TB). Indonesia menempati urutan 3 dunia dalam jumlah penderita TB. Menurut data di tahun 2004, lebih dari setengah juta rakyat Indonesia terserang tuberkolosis. Di Indonesia TB membunuh 1 orang setiap menit dan 140 ribu dalam setahun (Prasetyo, 2004). Data lain menyebutkan setiap hari 300 orang di Indonesia meninggal dunia akibat TB. Pada tahun 2007, diperkirakan kasus TB meningkat 5-6% dari total kasus yang ada. (Kompas, 20 April 2007) Penyakit tuberkolosis menjadi salah satu sebab tingginya angka kematian ibu melahirkan di Indonesia. Di dunia, setiap tahun, satu juta perempuan penderita TB meninggal saat kehamilan atau persalinan. Di Indonesia, lebih dari 50 persen kasus TB baru adalah perempuan, dan mayoritas perempuan penderita tuberkolosis paru berada dalam usia reproduktif.
Kematian bayi dan ibu melahirkan Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia termasuk tertinggi di kawasan Asia, yakni 307 per 100.000 kelahiran. Angka tersebut dicatat pada tahun 2003-2004, tidak jauh berbeda dengan Angka Kematian Ibu (AKI) pada 1994, yaitu sebesar 390 jiwa per 100.000 kelahiran hidup (Prasetyo, 2004). Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2002-2003 menemukan sebanyak 20.000 ibu meninggal dari 5 juta kelahiran setahun. Provinsi penyumbang kasus kematian ibu melahirkan terbesar ialah Papua yaitu 730 per 100.000 kelahiran, Nusa Tenggara Barat 370/100.000 kelahiran, Maluku 340 per 100.000 kelahiran, dan Nusa Tenggara Timur 330 per 100.000 kelahiran (Kompas, 20 November 2006). Selain provinsi-provinsi di atas, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) termasuk provinsi dengan AKI yang jauh lebih tinggi dari AKI nasional yaitu 517 jiwa per 100.000 kelahiran (Radar Sulteng, 7 November 2006). Seperti halnya kematian ibu melahirkan, kematian bayi di Indonesia juga berada dalam tingkat menggenaskan. Pada tahun 1991, Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 68 jiwa per 1.000 kelahiran hidup, dan di tahun 2002 dapat ditekan hingga 50% menjadi 35 jiwa setiap 1.000 kelahiran hidup (Prasetyo, 2004) Kurang Gizi, Gizi Buruk dan Busung Lapar Di dunia, kurang gizi menyebabkan kematian sekitar 6 juta anak balita setiap tahunnya (Population Reference Bureau, 2007). Di Indonesia, kurang gizi termasuk di dalam deretan persoalan kesehatan paling serius. Tercatat, di tahun 2006 sebanyak 2,3 juta anak balita di Indonesia menderita gizi buruk, meningkat dari 1,8 juta jiwa pada tahun 2006 (Kompas, 4 Oktober 2006). Di luar jumlah tersebut, masih terdapat lebih dari 5 juta anak balita menderita kurang gizi. Keseleruhan anak balita penderita gizi buruk dan kurang gizi tersebut mencapai 28% dari total balita di Indonesia. Sebanyak 10% dari jumlah tersebut berakhir dengan kematian. Jumlah ini adalah separuh dari Angka Kematian Bayi (AKB). Pada golongan anak usia sekolah, ditemukan dari 31 juta anak, 11 juta di antaranya bertubuh pendek akibat gizi kurang dan 10 juta mengalami anemia gizi. Untuk kelompok usia remaja, dari 10 juta remaja putri (15-19 tahun), sebanyak 3,5 juta mengalami anemia gizi. Untuk wanita usia subur (WUS), dari 118 juta WUS, sebanyak 11,5 juta di antaranya juga mengalami anemia gizi. Hal yang sama dialami ibu hamil. Sebanyak 1 juta dari total 4 juta ibu hamil pada tahun 2005 menderita Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan sekitar 2 juta menderita anemia gizi. Akibatnya rata-rata 350.000 bayi per tahun lahir dalam kondisi berat badan rendah.
Sementara itu, sekitar 30 juta orang dari kelompok usia produktif mengalami kurang energi kronis dan pada golongan penduduk lansia, jumlah penderita anemia gizi sekitar 5 juta orang (Kompas, 7 Oktober 2006). Laporan Unicef (2003) menyebutkan bahwa pada periode sebelum krisis ekonomi tahun 1997, kondisi anemia yang dialami perempuan hamil, anak balita dan anak usia sekolah di Indonesia berada dalam kondisi sangat mengkuatirkan, yaitu masing-masing mencapai 64%, 56% dan 30%. Jumlah ini meningkat drastic sejak krisis ekonomi. Di Jawa Tengah, prevalensi anemia meningkat dari 48% menjadi 65%, dan di pemukiman kumuh di Jakarta, penderita anemia anak usia sekolah meningkat lebih dari 85%. Kondisi ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Laporan Survei Departemen Kesehatan-Unicef tahun 2005, dari 343 kabupaten/kota hanya delapan kabupaten yang memiliki prevalensi balita gizi buruk atau gizi kurang yang rendah (kurang dari 10 persen). Sebanyak 257 kabupaten/kota lainnya tergolong prevalensi tinggi dan 169 kabupaten/kota sangat tinggi. Untuk persoalan ini, Nusa Tenggara Timur kembali menjadi salah satu juara. Pada tahun 2005, terdata 302 Kasus Luar Biasa (KLB) gizi buruk di 14 kabupaten/kota, sebanyak 297 kasus gizi buruk disertai kelainan klinis kekurangan karbohidrat (marasmus), satu kasus kekurangan protein (kwashiorkor) dan empat kasus marasmus-kwashiorkor. Dari total 463.920 orang balita yang ada di 16 kabupaten/kota se-NTT, 67.067 jiwa menderita gizi kurang dan 11.440 orang gizi buruk. Di tahun tersebut, 32 orang balita penderita gizi buruk meninggal dunia. Pada tahun 2006, di Kabupaten Sumba Barat, NTT, antara bulan Januari hingga September, sebanyak 25 orang dari 74 penderita gizi buruk yang dirawat di Rumah Sakit (RS) Charitas Weetabula, meninggal dunia akibat busung lapar. Kejadian ini berlangsung Januari hingga September 2006. Para pasien yang meninggal dunia pada umumnya karena terlambat mendapat pertolongan. Di Kabupaten Belu, temuan beberapa NGO pada tahun 2005, terdapat 30-50% anak balita kurang gizi, dan 1-3 % gizi buruk dari total seluruh balita yang ditimbang secara berkala. Belum termasuk jumlah sangat besar anak balita yang luput dari penimbangan berkala tersebut. Sementara hasil penimbangan terhadap 176.782 balita di Belu pada semester awal 2007, ditemukan 1.178 balita gizi buruk dan 6.583 gizi kurang. Hingga kini, jumlah penderita gizi buruk dan kurang gizi di NTT belum menunjukan kecendrungan berkurang. Dalam periode Januari hingga Maret 2008, ditemukan 106 anak busung lapar disertai kelainan klinis, 12.651 anak penderita gizi buruk tanpa gejala klinis dan 70.306 anak penderita gizi kurang. ***
Besarnya jumlah penderita berbagai macam penyakit dan kurang gizi di atas tentu tidak terjadi begitu saja. Ada persoalan serius dibelakangnya: kegagalan kebijakan pembangunan sektor kesehatan di Indonesia. Atau jika lebih jujur lagi: rendahnya kepedulian pemerintah terhadap pemenuhan hak asasi rakyat atas kesehatan.***Dipublikasi dalam Inisiatif (Newsletter bulanan Perkumpulan PIKUL) Edisi III, Maret 2008
http://www.nttzine.com/index.php/en/opini/83-negeri-seribu-satu-penyakit.html