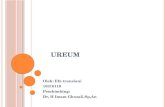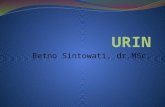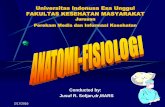FAKTOR DOMINAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN GAGAL … · meliputi : nilai GFR, ureum, dan kreatinin...
-
Upload
nguyennguyet -
Category
Documents
-
view
240 -
download
1
Transcript of FAKTOR DOMINAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN GAGAL … · meliputi : nilai GFR, ureum, dan kreatinin...

i
FAKTOR DOMINAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN
GAGAL GINJAL KRONIS PADA PASIEN
GAGAL GINJAL KRONIS
DI RSPAD GATOT SOEBROTO DITKESAD JAKARTA
FAHRUL ROZI
DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2016


iii
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER
INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Faktor Dominan yang
Berhubungan dengan Gagal Ginjal Kronis pada Pasien Gagal Ginjal Kronis di
RSPAD Gatot Soebroto adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi
pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun pada perguruan tinggi mana
pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan
maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan
dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.
Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut
Pertanian Bogor.
Bogor, Agustus 2016
Fahrul Rozi
NIM I14120012


v
ABSTRAK
FAHRUL ROZI. Faktor Dominan yang Berhubungan dengan Gagal Ginjal
Kronis pada Pasien Gagal Ginjal Kronis di RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad
Jakarta. Dibimbing oleh CESILIA METI DWIRIANI.
Penelitian bertujuan mengidentifikasi faktor dominan yang berhubungan
dengan gagal ginjal kronis pada pasien gagal ginjal kronis di RSPAD Gatot
Soebroto Ditkesad, Jakarta. Desain penelitian adalah cross sectional study dengan
contoh 35 orang, terdiri dari 19 laki-laki dan 16 perempuan. Contoh adalah pasien
gagal ginjal kronis yang melakukan hemodialisis di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta
dan berusia >18 tahun. Penelitian dilaksanakan pada Mei 2016. Penelitian ini
menggunakan data primer dan sekunder. Data primer meliputi: karakteristik contoh,
kebiasaan konsumsi pangan, berat badan dan tinggi badan, penyakit lain yang
berhubungan, dan gaya hidup dikumpulkan dengan wawancara. Data sekunder
meliputi : nilai GFR, ureum, dan kreatinin diperoleh dari data rekam medik pasien.
Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan tidak terdapat hubungan yang
signifikan (p>0.05) antara nilai GFR dengan: 1) kebiasaan merokok, 2) kebiasaan
konsumsi alkohol, 3) kebiasaan konsumsi gula, 4) kebiasaan konsumsi minuman
berenergi, dan 5) kebiasaan konsumsi suplemen. Akan tetapi penelitian ini
menemukan terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan konsumsi
suplemen (p=0.042) dan hubungan antara pendidikan dengan konsumsi suplemen
(p=0.018), serta hubungan antara nilai GFR dengan: 1) riwayat penyakit (p=0.000)
dan 2) status gizi (p=0.000). Hasil uji regresi linear menunjukkan bahwa besar
keluarga, asupan makanan asin dan awetan, konsumsi air putih, status gizi, dan
konsumsi gula merupakan faktor dominan yang berhubungan dengan gagal ginjal
kronis pada pasien gagal ginjal kronis di RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad Jakarta
(p=0.000)
Kata kunci : CKD, Gaya hidup, GFR, Kebiasaan makan, Status gizi
ABSTRACT
Fahrul Rozi. Dominant Factors Relate to CKD in Patients with CKD at
RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad Jakarta. Supervised by CESILIA METI
DWIRIANI.
This research was aimed to identify dominant factors related to chronic
kidney disease in patient with chronic kidney disease at RSPAD Gatot Soebroto
Ditkesad, Jakarta. This research used cross sectional design with 35 subjects
consists of 19 men and 16 women. Subjects were patients with chronic kidney
disease doing hemodyalisis in RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad Jakarta, aged >18
years old of man and woman. This research was conducted on Mei 2016. Primary
data and secondary data were used in this research. Primary data consists of
subjects characteristics, food habit, lifestyle, weight and height, and others diseases
related to CKD getting from interview, meanwhile secondary data getting from
patients medical records that consists of GFR value, ureum value, and creatinine
value.

Spearman correlation test showed that, there were no significantly
correlation among smoking habit, alcohol drinking habit, sugar consuming habit,
energy drinking habit, and supplement consumption habit with GFR value
(p>0.05). However, there were significantly correlation between age (p=0.042)
and education (p=0.018) with supplement consumption. There were significantly
correlation between others diseases related to CKD (p=0.000) and nutritional
status (p=0.000) with GFR value. The result of linear regression test showed that
family size, salted and preserved food intake, water drinking, nutrional status, and
sugar consuming habit were dominant factors related to CKD in RSPAD Gatot
Soebroto Ditkesad Jakarta (p=0.000).
Key words : CKD, Food habit, GFR, Lifestyle, Nutritional status

vii
FAKTOR DOMINAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN
GAGAL GINJAL KRONIS PADA PASIEN
GAGAL GINJAL KRONIS
DI RSPAD GATOT SOEBROTO DITKESAD JAKARTA
FAHRUL ROZI
Skripsi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Gizi
dari Program Studi Ilmu Gizi pada
Departemen Gizi Masyarakat
DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2016


Scanned by CamScanner

ix
Judul Skripsi : Faktor Dominan yang Berhubungan dengan Gagal Ginjal Kronis
pada Pasien Gagal Ginjal Kronis di RSPAD Gatot Soebroto
Ditkesad Jakarta
Nama : Fahrul Rozi
NIM : I14120012
Disetujui oleh
Dr. Ir. Cesilia Meti Dwiriani, M. Sc
Pembimbing
Diketahui oleh
Dr. Rimbawan
Ketua Departemen
Tanggal lulus:


xi
PRAKATA
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-
Nya karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema penelitian yang dipilih adalah
tentang gagal ginjal kronis, dengan judul Faktor Dominan yang Berhubungan
dengan Gagal Ginjal Kronis pada Pasien Gagal Ginjal Kronis di RSPAD Gatot
Soebroto Ditkesad Jakarta. Penelitian dilakukan pada Mei 2016 pada pasien gagal
ginjal kronis.
Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Ir. Cesilia Meti Dwiriani, M. Sc
selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi dan dr. Naufal
Muharam Nurdin selaku dosen penguji. Penulis juga mengucapkan terima kasih
kepada Bapak Samsu Rizal, Amk selaku Koordinator Unit Hemodialisis RSPAD
Gatot Soebroto Ditkesad Jakarta yang telah memberikan izin kepada penulis dalam
pengambilan data penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak
Abu Bakar dan Ibu Syamsiah sebagai orang tua, serta Sri Ningsih, dan Muhammad
Rifai sebagai kakak dan adik penulis yang telah memberikan doa dan dukungan
yang luar biasa kepada penulis. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada
seluruh teman-teman Gizi Masyarakat 47, 48, 49, dan 50 yang telah menjadi
keluarga penulis di Institut Pertanian Bogor dan senantiasa memberikan dukungan.
Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.
Bogor, Agustus 2016


xiii
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL Ixv
DAFTAR LAMPIRAN Ixv
PENDAHULUAN 1
Latar Belakang 1
Perumusan Masalah 2
Tujuan Penelitian 3
Hipotesis 3
Manfaat Penelitian 3
KERANGKA PEMIKIRAN 4
METODE 6
Desain, Tempat, dan Waktu Penelitian 6
Jumlah dan Cara Penarikan Contoh 6
Jenis dan Cara Pengumpulan Data 7
Pengolahan dan Analisis Data 8
Data Karakteristik Individu 9
Kebiasaan Konsumsi makan 9
Gaya Hidup 10
Penyakit Lain 10
Status Gizi 11
Gagal Ginjal Kronis 11
DEFINISI OPERASIONAL 11
HASIL DAN PEMBAHASAN 12
Gambaran Umum Rumah Sakit 12
Karakteristik Contoh 13
Jenis Kelamin 14
Usia 14
Agama 15
Pekerjaan 15
Tingkat Pendidikan 15
Pendapatan/Kap 15
Besar Keluarga 16
Gaya Hidup 16
Kebiasaan Merokok 17
Kebiasaan Konsumsi Alkohol 17
Kebiasaan Olahraga 17
Kebiasaan Makan 18
Konsumsi Makanan Sehat 18
Konsumsi Makanan Asin dan Awetan 23
Konsumsi Makanan Sumber Lemak 24
Konsumsi Bumbu dan Gula 24
Konsumsi Air Putih 25
Konsumsi Minuman Berenergi 25
Konsumsi Suplemen 26
Riwayat Penyakit 27
Status Gizi 28

xiv
Hubungan antar variabel 29
Hubungan Usia dengan Konsumsi Suplemen 29
Hubungan Pendidikan dengan Konsumsi Suplemen 30
Hubungan antara Nilai GFR dengan Gaya Hidup 30
Hubungan antara Nilai GFR dengan Kebiasaan Merokok 30
Hubungan antara nilai GFR dengan Kebiasaan Konsumsi Alkohol 31
Hubungan antara Nilai GFR dengan Kebiasaan Olahraga 31
Hubungan antara Nilai GFR dengan Kebiasaan Makan 32
Hubungan antara Nilai GFR dengan Kebiasaan Konsumsi
Makanan Asin dan Awetan
32
Hubungan antara Nilai GFR dengan Kebiasaan Konsumsi
Makanan Berlemak
32
Hubungan antara Nilai GFR dengan Kebiasaan Konsumsi Bumbu 32
Hubungan antara Nilai GFR dengan Kebiasaan Konsumsi Gula 33
Hubungan antara Nilai GFR dengan Kebiasaan Konsumsi Air
Putih
33
Hubungan antara Nilai GFR dengan Kebiasaan Konsumsi
Minuman Berenergi
33
Hubungan antara Nilai GFR dengan Kebiasaan Konsumsi
Suplemen
34
Hubungan antara Nilai GFR dengan Penyakit Lain yang Berhubungan 34
Hubungan antara Nilai GFR dengan Status Gizi 35
Faktor Dominan yang Berhubungan dengan CKD 35
SIMPULAN DAN SARAN 38
DAFTAR PUSTAKA 40
LAMPIRAN 43
DAFTAR TABEL
1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data 7
2 Pengelompokan Karakteristik Contoh 9
3 Pengelompokan Kebiasaan Makan Contoh 10
4 Pengelompokan Gaya Hidup Contoh 10
5 Pengelompokan Penyakit Lain Contoh 11
6 Pengelompokan Status Gizi Contoh 11
7 Penggolongan GFR, Ureum, dan Kreatinin 11
8 Sebaran Contoh berdasarkan Karakteristik Contoh 13
9 Sebaran Contoh berdasarkan Gaya Hidup Contoh 16
10 Sebaran Contoh berdasarkan Kebiasaan Makan Contoh 19
11 Kebiasaan Konsumsi Air Putih 25
12 Kebiasaan Konsumsi Minuman Berenergi 25
13 Sebaran Kebiasaan Konsumsi Suplemen 26
14 Sebaran Riwayat Kesehatan 27
15 Sebaran Status Gizi Contoh 29
16 Faktor Dominan yang Behubungan dengan CKD 36

xv
DAFTAR GAMBAR
1 Kerangka Pemikiran Faktor Dominan Gagal
Ginjal Kronis pada Pasien Gagal Ginjal
Kronis di RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad
Jakarta
5

1
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di
dunia masih menghadapi berbagai permasalahan kesehatan yang cukup pelik.
Selain masih menghadapi berbagai permasalahan yang lazim terjadi di negara-
negara berkembang, seperti kurang gizi, penyakit menular/penyakit tropis dan
infeksi, dll, Indonesia juga mulai menghadapi berbagai permasalahan kesehatan
yang lazim terjadi di negara-negara maju, yaitu penyakit-penyakit kronis akibat
proses degeneratif dan perubahan gaya hidup, seperti hipertensi, diabetes mellitus,
penyakit jantung koroner, gagal ginjal kronis, stroke, dll. Data Riskesdas tahun
2013 menunjukkan persentase penyakit tidak menular pada tahun 2013 sebanyak
42.2% dan salah satu penyakit tidak menular yang prevalensinya meningkat setiap
tahun adalah penyakit gagal ginjal kronis (chronic kidney disease (CKD))
(Kemenkes 2013).
Penyakit gagal ginjal kronis merupakan salah satu masalah kesehatan di
dunia. Ginjal memiliki fungsi vital yaitu untuk mengatur volume dan komposisi
kimia darah dengan mengekskresikan zat sisa metabolisme tubuh dan air secara
selektif. Apabila terjadi gangguan fungsi pada kedua ginjal maka ginjal akan
mengalami kematian dalam waktu 3 – 4 minggu. Hal ini dapat terjadi pada penyakit
ginjal kronis yang mengalami penurunan fungsi ginjal secara progresif dan
umumnya akan berakhir dengan gagal ginjal. Gagal ginjal itu sendiri menyebabkan
terjadinya penurunan fungsi ginjal yang progresif dan irreversible (Chadban et al.
2003).
Menurut data United State Renal Data System (USRDS) (2009), prevalensi
gagal ginjal kronis di Amerika Serikat yaitu sekitar 5 – 37% antara tahun 1980 –
2001. Pada tahun 2013 mencapai angka 50%. Menurut data Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas) tahun 2013 prevalensi gagal ginjal kronis di Indonesia sekitar 0.2%.
Prevalensi kelompok umur ≥75 tahun dengan 0.6% lebih tinggi daripada kelompok
umur yang lain. Prevalensi gagal ginjal kronis di Provinsi DKI Jakarta sebesar
0.1%.
Berdasarkan estimasi Badan Kesehatan Dunia (WHO), secara global lebih
dari 500 juta orang mengalami penyakit gagal ginjal kronis. Sekitar 1.5 juta orang
harus menjalani hidup bergantung pada cuci darah (Hemodialisis). Di Indonesia,
Pusat Data dan Informasi Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia melaporkan
jumlah pasien gagal ginjal kronis diperkirakan sekitar 50 orang per satu juta
penduduk, dimana 60% diantaranya adalah usia dewasa dan usia lanjut.
Berdasarkan data Indonesian Renal Registry (2011), suatu kegiatan registrasi dari
Perhimpunan Nefrologi Indonesia, pada tahun 2007 jumlah pasien hemodialisis
mencapai 2148 orang, dan meningkat pada tahun 2008 menjadi 2260 orang. Salah
satu faktor penyebab meningkatnya angka penderita gagal ginjal di dunia adalah
kurangnya kesadaran masyarakat terhadap deteksi dini penyakit tersebut (John et
al. 2004).
Pasien dengan gagal ginjal kronis akan mengalami kerusakan fungsi ginjal
yang parah dan kronis yang mengakibatkan pasien sulit ditolong. Salah satu
penanganan yang tepat untuk pasien gagal ginjal kronis adalah berupa terapi

2
pengganti ginjal, dimana yang sering dilakukan adalah Hemodialisis. Hemodialisis
merupakan metode cuci darah menggunakan mesin ginjal buatan. Prinsip
hemodialisis adalah dengan membersihkan dan mengatur kadar plasma darah yang
nantinya akan digantikan oleh mesin ginjal buatan. Biasanya hemodialisis
dilakukan rutin 2-3 kali seminggu selama 4-5 jam. Pada hemodialisis dibutuhkan
dana yang banyak dan dalam menjalani hemodialisis akan terdapat banyak
komplikasi dimana salah satunya adalah timbulnya gizi kurang (Fox et al. 2004).
Penyakit gagal ginjal kronis terjadi melalui proses yang panjang (bertahun
– tahun). Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit gagal ginjal
kronis adalah diabetes mellitus, hipertensi, glomerulonephritis, penyakit jantung,
kanker, batu ginjal, dll yang secara tidak langsung disebabkan oleh konsumsi
pangan yang tidak baik, seperti konsumsi pangan siap saji yang mengandung lemak
tinggi, konsumsi pangan dengan kandungan garam tinggi, dan rendahnya konsumsi
buah dan sayur. Selain itu, gaya hidup seperti merokok, konsumsi alkohol, dan
rendahnya aktivitas fisik juga menjadi faktor dominan yang berhubungan dengan
penyakit gagal ginjal kronis (Haroun et al. 2003).
Unit Hemodialisis RSPAD Gatot Soebroto merupakan salah satu pelayanan
yang terdapat di RSPAD Gatot Soebroto. Rata-rata pasien yang melakukan
hemodialis di Unit Hemodialisis RSPAD Gatot Soebroto sekitar 80 orang/hari.
Penyakit gagal ginjal kronis seharusnya menjadi perhatian serius mengingat
semakin tingginya prevalensi penyakit gagal ginjal kronis di Jakarta, khususnya di
RSPAD Gatot Soebroto, banyaknya komplikasi yang dialami, dan kerugian yang
dialami oleh pasien dengan penyakit gagal ginjal kronis. Oleh karena itu, peneliti
tertarik untuk meneliti Faktor Dominan yang Berhubungan dengan Terjadinya
Penyakit Gagal Ginjal Kronis pada Pasien Gagal Ginjal Kronis di RSPAD Gatot
Soebroto Ditkesad.
Perumusan Masalah
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Bagaimana karakteristik pasien gagal ginjal kronis?
2. Bagaimana gaya hidup pasien gagal ginjal kronis sebelum mengalami gagal
ginjal kronis?
3. Bagaimana kebiasaan makan pasien gagal ginjal kronis sebelum mengalami
gagal ginjal kronis ?
4. Adakah penyakit lain (komplikasi) yang diderita oleh pasien gagal ginjal kronis?
5. Apakah karakteristik contoh berhubungan dengan kebiasaan makan?
6. Apakah gaya hidup dan kebiasaan makan contoh sebelum mengalami gagal
ginjal kronis berhubungan dengan nilai GFR atau penyakit gagal ginjal kronis?
7. Apa saja faktor dominan yang berhubungan dengan gagal ginjal kronis?

3
Tujuan
Tujuan Umum
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor dominan
yang berhubungan dengan gagal ginjal kronis pada pasien gagal ginjal kronis di
RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad Jakarta.
Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah
1. Mengidentifikasi karakteristik pasien gagal ginjal kronis
2. Mengidentifikasi gaya hidup pasien gagal ginjal kronis
3. Mengidentifikasi kebiasaan makan pasien gagal ginjal kronis
4. Mengidentifikasi penyakit lain (komplikasi) yang diderita pasien gagal ginjal
kronis
5. Menganalisis hubungan antara karakteristik contoh dengan kebiasaan makan
6. Menganalisis hubungan antara gaya hidup dan kebiasaan makan pasien dengan
nilai GFR
7. Menganalisis faktor dominan yang berhubungan dengan gagal ginjal kronis
Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Terdapat hubungan antara karakteristik contoh dengan kebiasaan makan contoh
2. Terdapat hubungan antara gaya hidup dengan nilai GFR pasien gagal ginjal
kronis
3. Terdapat hubungan antara kebiasaan makan dan penyakit lain (komplikasi)
dengan nilai GFR pasien gagal ginjal kronis
Manfaat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi
mengenai faktor dominan yang berhubungan dengan gagal ginjal kronis pada
pasien gagal ginjal kronis di RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad, Jakarta. Bagi
pemerintah maupun instansi yang terkait dapat dijadikan dasar perencanaan
program atau kebijakan dalam upaya pencegahan dan pengelolaan terhadap
penyakit gagal ginjal kronis. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan
bahan perbandingan untuk penelitian – penelitian selanjutnya yang terkait dengan
faktor dominan yang berhubungan dengan gagal ginjal kronis pada pasien gagal
ginjal kronis.

4
KERANGKA PEMIKIRAN
Gagal ginjal kronis adalah masalah kesehatan utama di dunia. Gagal ginjal
kronis merupakan tahap akhir dari penyakit ginjal yang terjadi selama bertahun –
tahun. Penyakit gagal ginjal kronis ditandai dengan laju filtrasi glomerulus kurang
dari 60 mL/menit/1.73 m2, kadar ureum, kreatinin, asam urat, kalium, dan natrium
yang tinggi, seringkali disertai dengan anemia dan edema. Banyak faktor yang
menyebabkan terjadinya gagal ginjal kronis, diantaranya konsumsi pangan, gaya
hidup (kebiasaan merokok, kebiasaan konsumsi alkohol, dan kebiasaan olahraga),
serta penyakit lain.
Konsumsi pangan menjadi faktor dominan yang berhubungan dengan
terjadinya penyakit gagal ginjal kronis. Konsumsi pangan seseorang dipengaruhi
oleh banyak faktor, diantaranya usia, pendidikan, pendapatan, besar keluarga, dan
pekerjaan. Konsumsi pangan yang tidak baik, seperti konsumsi makanan yang
terlalu asin, terlalu manis, berlemak tinggi, mengandung tinggi kalori, dan
kebiasaan konsumsi air secara tidak langsung dan dalam waktu lama akan membuat
kerja ginjal tidak optimal. Kerja ginjal tidak optimal diawali dengan kehadiran
beberapa penyakit lain karena konsumsi makanan yang tidak baik. Konsumsi
makanan asin berimplikasi pada hipertensi, konsumsi makanan manis berimplikasi
pada diabetes mellitus, dan konsumsi makanan tinggi kalori dan lemak akan
berimplikasi pada obesitas. Ginjal akan melakukan upaya adaptif dalam beberapa
saat terhadap keadaan tersebut, namun ketika kerja ginjal semakin berat maka ginjal
tidak mampu lagi untuk melakukan kerjanya.
Gaya hidup akan menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kondisi
kesehatan tubuh, salah satunya keadaan ginjal . Penyakit gagal ginjal kronis sangat
berkaitan dengan gaya hidup seseorang. Aktivitas fisik merupakan serangkaian
kegiatan yang dilakukan oleh otot motorik tubuh untuk membuat keseimbangan
proses metabolisme dalam tubuh. Biasanya aktivitas fisik yang baik akan
berimplikasi terhadap status gizi baik. Aktivitas fisik yang baik menunjukkan gaya
hidup yang baik pula. Kebiasaan merokok dan minum alkohol merupakan pola gaya
hidup buruk yang dapat memberikan respon negatif terhadap kesehatan tubuh,
terutama pada ginjal. Oleh karena itu penelitian ini berusaha menggali informasi
mengenai faktor dominan yang berhubungan dengan gagal ginjal kronis. Kerangka
pemikiran dari penelitian ini disajikan pada Gambar 1.

5
\
Keterangan:
= Variabel yang diteliti
= = Variabel yang tidak diteliti
= Hubungan yang dianalisis
= Hubungan yang tidak dianalisis
Gambar 1 Kerangka pemikiran faktor dominan yang berhubungan dengan gagal
ginjal kronis pada pasien gagal ginjal kronis
Penyakit lain:
Hipertensi
DM
Karakteristik contoh:
Usia
Jenis Kelamin
Pendidikan
Pendapatan
Besar keluarga
Pekerjaan
Kebiasaan makan
Kebiasaan konsumsi
makanan asin, tinggi lemak,
manis, dan bumbu
Kebiasaan konsumsi air
Konsumsi minuman
berenergi
Konsumsi supplemen
Gagal ginjal kronis
-
-Nilai GFR abnormal
-Nilai kreatinin abnormal
-
-
-
- Nilai kreatinin
abnormal
Status Gizi
(IMT)
Gaya hidup:
Kebiasaan
merokok
Kebiasaan minum
alkohol
Kebiasaan
olahraga
Herediter

6
METODE
Desain, Tempat, dan Waktu
Penelitian menggunakan desain cross sectional study dan dilaksanakan di
ruang hemodialisis RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad Jakarta. Lokasi ini dipilih
secara purposive dengan pertimbangan jumlah pasien gagal ginjal kronis yang
melakukan hemodialisis dan dirawat inap cukup banyak, serta diperbolehkan oleh
pihak Rumah Sakit untuk mendapatkan data pasien. Penelitian ini dilaksanakan
pada Mei 2016.
Jumlah dan Cara Penarikan Contoh
Populasi pada penelitian ini adalah pasien dewasa yang menjalani
hemodialisis di unit hemodialisis RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad, Jakarta. Contoh
diambil dari pasien gagal ginjal kronis yang melakukan hemodialisis dan bersedia
untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Adapun kriteria inklusi dari penelitian
adalah:
1. Pasien rawat inap dan rawat jalan dewasa pria dan wanita, berumur >18 tahun
2. Penderita gagal ginjal kronis, yang ditunjukkan dengan nilai GFR <60
mL/menit, nilai ureum abnormal (N:10-50 mg/dL), dan nilai kreatinin abnormal
(N:<1.5 mg/dL)
3. Tidak sedang mengalami odeme (penumpukan cairan)
4. Bersedia untuk menjadi contoh dalam penelitian ini
Penentuan jumlah contoh minimal penelitian ini dihitung berdasarkan
rumus perhitungan Lemeshow et al. (1997). Berdasarkan data Riset Kesehatan
Dasar (Riskesdas) pada tahun 2013, prevalensi penderita gagal ginjal kronis di
Indonesia adalah 0.2%. Rumus untuk menentukan jumlah contoh minimal adalah
sebagai berikut.
n ≥ [(𝑍
1−∝2
) 𝑥 𝑝 (1−𝑝)]
𝑑2
Keterangan:
n = Jumlah contoh minimal
p = Prevalensi penderita gagal ginjal kronis di Indonesia, yakni 0.2%
q = 1-p
d = Presisi yang diinginkan/limit error (10%)
z = Derajat kepercayaan 10% →90% (Z1-α/2 = 1.28)
Berdasarkan rumus tersebut maka jumlah contoh minimal adalah:
n ≥ [(1.28)2𝑥 0.002 (1−0.002)
0.12
n ≥ 32.7 ≈ 33 orang
Mengantisipasi adanya contoh yang di drop-out, maka jumlah contoh
ditambah 10%, sehingga menjadi 36 orang.

7
Jenis dan Cara Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan mencakup data primer dan sekunder. Data primer
meliputi: 1) Karakteristik contoh (usia, pendidikan, pendapatan, besar keluarga, dan
pekerjaan), 2) Kebiasaan konsumsi pangan, 3) Antropometri (berat badan dan
tinggi badan), dalam kondisi pasien tidak dapat berdiri maka data lingkar lengan
atas dan tinggi lutut diperlukan untuk estimasi berat badan dan tinggi badan, dan 4)
Gaya hidup (kebiasaan merokok, kebiasaan minum alkohol, dan kebiasaan
olahraga). Data sekunder diperoleh dari Rumah Sakit yaitu nilai laboratorium yang
berhubungan dengan gagal ginjal kronis meliputi nilai GFR, ureum, kreatinin, dan
data penyakit lain, diantaranya hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, batu
ginjal, dll.
Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan pengisian kuesioner.
Data sekunder dikumpulkan dengan cara pencatatan dari hasil rekam medik pasien.
Adapun jenis dan cara pengumpulan data secara ringkas disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1 Jenis dan cara pengumpulan data
Variabel Jenis Data Cara Pengumpulan
Karakteristik contoh 1. Usia
2. Jenis kelamin
3. Pendidikan
4. Pendapatan keluarga
5. Besar keluarga
6. Pekerjaan
Wawancara
menggunakan
kuesioner
Kebiasaan konsumsi
pangan
1. Frekuensi makan
2. Kebiasaan konsumsi
makanan asin dan
awetan, makanan
manis, bumbu, dan
makanan berlemak
3. Kebiasaan konsumsi
air
4. Kebiasaan konsumsi
minuman berenergi
5. Kebiasaan konsumsi
supplemen
Metode semi
quantitative food
frequency (SQ-FFQ)
Status Gizi 1. Berat badan (Kg)
2. Tinggi badan (m)
3. LILA (Cm)
4. TILUT (Cm)
Pengukuran berat
badan menggunakan
timbangan injak, tinggi
badan menggunakan
microtoise, LILA
menggunakan pita
LILA, dan TILUT
menggunakan
meterline

8
Gaya hidup 1. Kebiasaan merokok
2. Kebiasaan minum
alcohol
3. Kebiasaan olahraga
Wawancara
menggunakan
kuesioner
Penyakit lain 1. Hipertensi
2. DM
3. Penyakit jantung
Pencatatan hasil rekam
medis
Gagal ginjal kronis 1. Nilai GFR
(Glomerular
Filtration Rate)
2. Nilai ureum
3. Nilai kreatinin
Pencatatan hasil rekam
medis
Karakteristik contoh (usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan keluarga,
besar keluarga, dan pekerjaan) diperolah melalui wawancara menggunakan
kuesioner. Kebiasaan konsumsi pangan pasien terdiri atas kebiasaan konsumsi
makanan asin dan awetan, makanan berlemak, bumbu, dan makanan manis
diperoleh melalui wawancara menggunakan semi quantitative food frequency
questionnaire (SQ-FFQ).
Status gizi (Indeks masa tubuh/IMT), lingkar lengan atas, dan tinggi lutut
diperoleh dari pengukuran contoh secara langsung. Berat badan diukur
menggunakan timbangan injak (kapasitas 200 Kg dengan ketelitian 0.1 Kg) dan
pengukuran tinggi badan menggunakan microtoise (kapasitas 200 cm dengan
ketelitian 0.1 cm). Pengukuran lingkar lengan atas dan tinggi lutut diukur
menggunakan meterline (kapasitas 200 cm dan ketelitian 0.1 cm). Pengukuran berat
badan dan tinggi badan dilakukan sebelum hemodialisis, sedangkan pengukuran
LILA dan TILUT dilakukan ketika pasien sedang hemodialisis.
Data kebiasaan olahraga, kebiasaan minum alkohol, dan kebiasaan merokok
diperoleh melalui wawancara menggunakan semi kuantitatif kuesioner. Data
penyakit lain pasien diperoleh melalui pencatatan data rekam medis. Data nilai
GFR, ureum, dan kreatinin contoh diperoleh dari pencatatan hasil rekam medis.
Nilai GFR diperoleh sebelum pasien melakukan hemodialisis dengan pertimbangan
nilai GFR saat itu menunjukkan fungsi ginjal yang sebenarnya. Nilai GFR dihitung
menggunakan rumus Stump (2004) berikut.
GFR = (140−𝑢𝑚𝑢𝑟)𝑥 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛 𝑥 (0.85=𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛)
72 𝑥 𝑠𝑒𝑟𝑢𝑚 𝑘𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑖𝑛
Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan data menggunakan program Microsoft Excell 2013 dan SPSS
version 16.0 for windows. Tahap pengolahan data meliputi entry, coding, cleaning,
pengkategorian data, dan analisis data. Analisis data yang dilakukan meliputi
analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Analisis univariat dilakukan untuk
mendeskripsikan seluruh variabel penelitian, meliputi karakteristik contoh,
kebiasaan makan contoh, gaya hidup contoh, status gizi, dan riwayat kesehatan
contoh. Uji deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai minimal, nilai maksimal,
nilai rata-rata, median, dan standar deviasi. Analisis bivariat digunakan untuk
Tabel 3 Jenis dan Cara Pengambilan Data (Lanjutan)
Tabel 1 Jenis dan cara pengumpulan data (Lanjutan)

9
melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dipenden. Uji korelasi
Pearson dan Spearman digunakan untuk melihat hubungan antara variabel
independen dan variabel dipenden. Analisis multivariat digunakan untuk melihat
faktor dominan yang berhubungan dengan gagal ginjal kronis. Analisis multivariat
yang digunakan adalah uji regresi linear.
Data Karakteristik Individu
Data karakteristik contoh yang dikumpulkan meliputi usia, jenis kelamin,
tingkat pendidikan, pendapatan keluarga, besar keluarga, dan pekerjaan. Data
tersebut selanjutnya dikelompokkan dan dianalisis secara deskriptif.
Pengelompokan karakteristik contoh secara keseluruhan disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2 Pengelompokan karakteristik contoh
No. Variabel Kelompok Sumber Acuan
1 Usia 1. <45 tahun
2. ≥45 tahun
Wong et.al
(2014)
2 Jenis Kelamin 1. Laki-laki
2. Perempuan
Ketentuan
peneliti
3 Tingkat
pendidikan
1. Tidak pernah
sekolah
2. Tidak tamat SD
3. Tamat SD
4. Tamat SMP
5. Tamat SMA
6. Tamat PT
WHO STEPS
4 Pendapatan
keluarga per
bulan (Rp)
1. <Rp 487.388,00
2. ≥Rp 487.388,00
UMR Provinsi
DKI Jakarta
2016
5 Besar keluarga 1. Keluarga kecil
(≤4 orang)
2. Keluarga sedang
(5-7 orang)
3. Keluarga besar
(≥7 orang)
BKKBN (1998)
6 Pekerjaan 1. Tidak bekerja
2. PNS/ABRI
3. Wiraswasta
4. Buruh
5. Jasa
6. Pensiun
7. Lainnya
Ketentuan
peneliti
Kebiasaan Konsumsi Makan
Kebiasaan konsumsi makan yang diteliti meliputi frekuensi makan,
kebiasaan konsumsi makanan asin dan awetan, kebiasaan konsumsi makanan
berlemak, kebiasaan konsumsi bumbu, kebiasaan konsumsi makanan manis,
kebiasaan konsumsi air, kebiasaan konsumsi minuman berenergi, dan kebiasaan

10
konsumsi supplemen. Pengelompokan kebiasaan konsumsi makanan contoh
disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3 Pengelompokan kebiasaan makan contoh
No. Variabel Kelompok Sumber Acuan
1 Kebiasaan konsumsi
makanan asin dan
awetan
1. Tidak sering (<7 kali/minggu)
2. Sering (≥7 kali/minggu)
Riskesdas 2013
2 Kebiasaan konsumsi
makanan manis
1. Tidak sering (<7 kali/minggu)
2. Sering (≥7 kali/minggu)
Riskesdas 2013
3 Kebiasaan konsumsi
makanan berlemak
1. Tidak sering (<7 kali/minggu)
2. Sering (≥7 kali/minggu)
Riskesdas 2013
4 Kebiasaan konsumsi
bumbu
1. Tidak sering (<7 kali/minggu)
2. Sering (≥7 kali/minggu)
Riskesdas 2013
5 Kebiasaan konsumsi
air
1. <8 gelas/hari
2. ≥8 gelas/hari
Ketentuan
peneliti
6 Kebiasaan konsumsi
minuman berenergi
1. Tidak
2. Ya
Ketentuan
peneliti
7 Kebiasaan konsumsi
supplemen
1. Tidak
2. Ya
Ketentuan
peneliti
Gaya Hidup
Variabel gaya hidup meliputi kebiasaan merokok, kebiasaan konsumsi
alkohol, dan kebiasaan olahraga. Menurut Cade et al. (1984), kebiasaan olahraga
yang baik minimal 3 kali dalam seminggu dengan durasi minimal 30 menit setiap
kali berolahraga. Pengelompokan gaya hidup contoh disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4 Pengelompokan gaya hidup contoh
No. Variabel Kelompok Sumber Acuan
1 Kebiasaan merokok 1. Tidak
2. Ya
Ketentuan peneliti
2 Kebiasaan konsumsi
allkohol
1. Tidak
2. Ya
Ketentuan peneliti
3 Kebiasaan olahraga 1. Tidak sering (<3
kali/seminggu)
2. Sering (≥3
kali/seminggu)
Cade et.al (1984)
Penyakit Lain
Penyakit lain yang diteliti dan menjadi batasan faktor dominan yang
berhubungan dengan gagal ginjal kronis pada penelitian ini adalah hipertensi,
diabetes mellitus, dan komplikasi keduanya. Pengelompokan penyakit lain
disajikan pada Tabel 5.

11
Tabel 5 Pengelompokan penyakit lain contoh
No. Variabel Kelompok Sumber Acuan
1 Penyakit lain 1. Tidak ada
2. Ada
Ketentuan peneliti
Status Gizi
Penentuan status gizi contoh dikategorikan berdasarkan IMT (indeks masa
tubuh). Penggolongan IMT berdasarkan acuan WHO (2000) untuk orang Asia.
Penggolongan status gizi disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6 Penggolongan status gizi contoh
No. Variabel Kelompok Sumber Acuan
1 IMT (Kg/m2) 1. Underweight (<18.5 Kg/m2)
2. Normal (18.5-22.9 Kg/m2)
3. At Risk (23-24.9 Kg/m2)
4. Obese I (25-29.9 Kg/m2)
5. Obese II (≥30 Kg/m2)
WHO (2000)
Gagal Ginjal Kronis
Penyakit CKD ditandai dengan nilai GFR, ureum, dan kretainin yang tidak
normal. Penggolongan GFR, ureum, dan kreatinin disajikan pada Tabel 7.
Tabel 7 Penggolongan GFR, ureum, dan kreatinin
No. Variabel Kelompok Sumber Acuan
1. GFR 1. Normal (90-120 mL/menit)
2. CKD (<60 mL/menit)
Almatsier (2006)
2. Ureum 1. Rendah (<10 mg/dL)
2. Normal (10-50 mg/dL)
3. Tinggi (>50 mg/dL)
Almatsier (2006)
3. Kreatinin 1. Normal (<1.5 mg/dL)
2. Tidak normal (>1.5 mg/dL)
Almatsier (2006)
Definisi Operasional
Faktor dominan merupakan faktor terbesar yang memungkinkan terjadinya suatu
penyakit yang dapat mempercepat atau memperburuk penyakit. Gagal ginjal kronis merupakan suatu keadaan dimana ginjal tidak dapat berfungsi
secara optimal, yang ditandai dengan laju glomerulus filtrasi kurang dari 60
mL/menit/1.73 m2, nilai ureum >10-50 mg/dL, dan kadar kreatinin >1.5
mg/dL.
Glomerulus Filtration Rate merupakan laju glomerulus dalam memfiltrasi zat-zat
sisa metabolisme tubuh.
Kreatinin adalah sisa dari metabolisme kretinin posfat di otot dengan nilai normal
<1.5 mg/dL. Jika kadarnya tidak normal mengindikasikan ada kerusakan pada
ginjal.

12
Ureum merupakan hasil akhir metabolisme protein dengan nilai normal 10-50
mg/dL. Jika kadarnya tidak normal mengindikasikan ada kerusakan pada
ginjal.
Karakteristik contoh merupakan kondisi seseorang yang memengaruhi konsumsi
pangan dan gaya hidup terdiri atas usia, pendidikan, pendapatan, besar
keluarga, dan pekerjaan.
Pekerjaan adalah jenis aktivitas yang mendatangkan penghasilan utama contoh.
Tingkat pendidikan merupakan pendidikan tertinggi yang telah diselesaikan oleh
contoh.
Besar keluarga merupakan jumlah semua orang yang tinggal dalam satu rumah
dan menggunakan sumber daya yang sama untuk memenuhi kebutuhannya.
Gaya hidup merupakan kebiasaan contoh dalam melakukan aktivitas fisik,
kebiasaan merokok, kebiasaan minum alkohol, dan kebiasaan olahraga.
Kebiasaan makan merupakan kecenderungan konsumsi makan contoh yang
menjadi kebiasaan. Dalam hal ini kebiasaan makan contoh, meliputi frekuensi
makan, kebiasaan konsumsi makanan asin dan awetan , kebiasaan konsumsi
makanan berlemak, kebiasaan konsumsi bumbu, kebiasaan konsumsi
makanan, kebiasaan konsumsi air putih, kebiasaan konsumsi suplemen, dan
kebiasaan konsumsi minuman berenergi.
Indeks Masa Tubuh (IMT) merupakan suatu rumus matematis untuk menentukan
status gizi seseorang dengan persamaan yaitu berat badan aktual (kilogram)
dibagi dengan kuadrat tinggi badan (meter kuadrat) atau IMT = (BB/(TB2).
Obesitas merupakan kondisi dimana IMT contoh lebih besar sama dengan 25
Kg/m2.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Rumah Sakit Gatot Soebroto Ditkesad Jakarta
Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Ditkesad Jakarta
merupakan rumah sakit rujukan tertinggi bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) di
seluruh Indonesia. RSPAD terletak di Jalan Abdul Rahman Saleh No. 24, Jakarta
Pusat. RSPAD dibangun oleh pemerintah Belanda dan dikenal sebagai Groot
Militaire Hospital Weltevreden. Awalnya, RSPAD digunakan bagi tentara Belanda,
selanjutnya pada zaman Jepang rumah sakit ini pernah pula digunakan bagi
Angkatan Darat Jepang yang disebut Rigukun Byoin. Kemudian, semenjak
Indonesia merdeka, RSPAD dikuasai oleh KNIL dan namanya diganti menjadi
Geneeskundige Dienst yang dikenal dengan nama Leger Hospital Batavia. Pada
tanggal 26 Juli 1950, RSPAD diserahkan kepada Djawatan Kesehatan Angkatan
Darat menjadi rumah sakit tentara pusat. Nama Gatot Soebroto dicantumkan di
belakang nama Rumah Sakit Angkatan Darat ini adalah sebagai apresiasi bagi
Letnan Jenderal Gatot Soebroto atas jasa – jasanya yang telah memberikan
segalanya bagi RSPAD dalam meningkatkan kesejahteraan Prajurit Angkatan Darat
(Khairunnisa 2012).
Sejak tahun 1989, RSPAD Gatot Soebroto mulai membuka pelayanan
swasta yang dikenal sebagai paviliun dr. Darmawan di bagian rawat inap.

13
Selanjutnya tahun 1991 dibangun paviliun Kartika yang terdiri atas 6 lantai yang
ditujukan bagi rawat jalan dan rawat inap. Kemudian dibangun dan diresmikan
paviliun dr. Irman Sudjudi yang melayani kesehatan ibu dan bayi, paviliun anak,
serta non paviliun untuk perawatan kelas tiga. RSPAD saat ini memiliki pelayanan
kesehatan yang dilayani oleh dokter spesialis dan sub spesialis dengan didukung
pelayanan, seperti Minimal Invasife Arthroscopy, Endoscopy Spine Surgery, MRI
1.5 Tesla, Linac Ct Simulator, Digital Substraction Angiography 3D (dsa-3D),
USG 3 dimensi, dan keperawatan bedah (Khairunnisa 2012).
Unit Hemodialisis RSPAD Gatot Soebroto merupakan salah satu pelayanan
yang terdapat di RSPAD. Unit ini dipimpin oleh satu orang kepala ruangan, yang
berkoordinasi dengan tim dokter, dibantu oleh 24 perawat yang waktu kerjanya
memiliki pembagian tersendiri berdasarkan shift jam kerja. Pada saat bekerja,
perawat dibantu oleh mahasiswa keperawatan yang sedang melakukan praktek
kerja lapang (PKL). Untit hemodialisis RSPAD memiliki 3 ruangan utama, ruang
hemodialisis I, ruang hemodialisis II, dan ruang hemodialisis III. Ruang
hemodialisis I ditujukan untuk pasien dengan penyakit infeksius yang terdiri atas
10 bed, ruang hemodialisis II merupakan ruang VIP yang terdiri atas 20 bed, dan
ruang hemodialisis III ditujukan untuk kelas I, II, dan III yang terdiri atas 30 bed
(Khairunnisa 2012).
Karakteristik Contoh
Tabel 8 menunjukkan data sebaran contoh berdasarkan jenis kelamin, usia,
agama, pekerjaan, tingkat pendidikan, pendapatan, dan besar keluarga contoh.
Tabel 8 Sebaran contoh laki-laki dan perempuan berdasarkan usia, agama,
pekerjaan, tingkat pendidikan, pendapatan, dan besar keluarga
Karakteristik contoh n %
Kelompok usia Laki-laki Perempuan
n % n %
<45 tahun 4 21.1 6 37.5
≥45 tahun 15 78.9 10 62.5
Total 19 100 16 100
Agama
Islam 19 100 14 87.5
Kristen 0 0 1 6.3
Katolik 0 0 1 6.3
Total 19 100 16 100

14
Tabel 8 Sebaran contoh laki-laki dan perempuan berdasarkan usia, agama,
pekerjaan, tingkat pendidikan, pendapatan, dan besar keluarga (Lanjutan)
Laki-laki Perempuan
n % n %
Pekerjaan
Tidak bekerja 1 5.3 12 75
PNS/ABRI 9 47.4 2 12.5
Wiraswasta 3 15.8 1 6.3
Pensiun 3 15.8 0 0
Lainnya 3 15.8 1 6.3
Total 19 100 16 100
Tingkat Pendidikan
Tamat SD 1 5.3 1 6.3
Tamat SMP 1 5.3 3 18.8
Tamat SMA 11 57.9 8 50
Tamat PT 6 31.6 4 25
Total 19 100 16 100
Pendapatan/Kapita/bln
≤Rp 487.388,00 18 94.7 13 81.3
>Rp 487.388,00 1 5.3 3 18.8
Total 19 100 16 100
Besar Keluarga
Kecil (≤4 orang) 10 52.6 11 68.8
Sedang (5-7 orang) 6 31.6 3 18.8
Besar (≥8 orang) 3 15.8 2 12.5
Total 19 100 16 100
Contoh berjenis kelamin laki-laki lebih besar, yaitu 19 orang (54.3%)
dibandingkan contoh perempuan, yaitu 16 orang (45.4%). Berdasarkan uji shapiro-
wilk, diperoleh nilai signifikansi p=0.000 (p<0.005) yang menunjukkan bahwa
sebaran data jenis kelamin menyebar tidak normal. Tabel 8 menunjukkan bahwa
sebagian besar contoh laki-laki (78.9%) berusia ≥45 tahun dan sebagian besar
contoh perempuan (62.5%) berusia ≥45. Berdasarkan uji shapiro-wilk, diperoleh
nilai signifikansi p=0.404 (p>0.05) yang menunjukkan bahwa data tersebut
menyebar normal. Contoh dengan usia paling rendah adalah 25 tahun dan contoh
dengan usia paling tinggi adalah 70 tahun. Menurut Coresh (2005), setelah umur 30
tahun, laju filtrasi glomerulus akan menurun drastis kira-kira 8 mL/menit/1.73 m2
per dekade. Penurunan laju filtrasi glomerulus akan berdampak terhadap kerusakan
ginjal. Sebagian besar contoh beragama islam, yaitu 19 laki-laki (100%) dan 14
perempuan (87.5%).
Sebanyak 47.4% contoh laki-laki memiliki pekerjaan PNS/ABRI dan
sebagian besar contoh perempuan (75%) termasuk ke dalam kategori tidak bekerja.
Contoh yang masuk ke dalam kategori lainnya adalah pegawai KRL, kariawan, dan
manager practice. Berdasarkan uji shapiro-wilk, diperoleh nilai signifikansi
p=0.000 (p<0.05) yang menunjukkan bahwa data tersebut menyebar tidak normal.
Sebagian besar contoh laki-laki (89.5%) dan perempuan (75%) memiliki
pendidikan terakhir SMA dan PT. Berdasarkan uji shapiro-wilk, diperoleh nilai

15
signifikansi p=0.000, yang menunjukkan bahwa sebaran data pendidikan tidak
menyebar normal.
Pendapatan per kapita merupakan rata – rata pendapatan untuk setiap
individu atau untuk setiap anggota keluarga yang diperoleh dengan
membandingkan rata – rata pendapatan rumah tangga per bulan dengan jumlah
anggota keluarga pada suatu wilayah kota tertentu (Aufa 2013). Pada penelitian ini
pendapatan/kap dihubungkan dengan garis kemiskinan. Ukuran garis kemiskinan
yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) berdasarkan pendekatan
kemiskinan absolut, dengan mengacu pada definisi kemiskinan oleh Sayogyo
(2000). Menurut Sayogyo (2002), seseorang dikatakan miskin secara absolut
apabila pendapatannya lebih rendah dari garis kemiskinan absolut atau dengan
istilah lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup
minimum. Menurut BPS (2015), Garis kemiskinan untuk DKI Jakara tahun 2015
adalah Rp 487.388,00 per kapita per bulan.
Pendapatan/kap dikategorikan menjadi 2 kategori, yaitu miskin dan tidak
miskin. Sebagian besar contoh berada di bawah garis kemiskinan, yaitu 18 laki-laki
(94.7%) dan 13 perempuan (81.3%). Contoh yang berada di atas garis kemiskinan
adalah 1 laki-laki (5.3%) dan 3 perempuan (18.8%). Median dari pendapatan/kap
adalah 1125000. Pendapatan per kapita tertinggi adalah Rp 4000.000,00 dan
pendapatan terendah adalah Rp 3.12500,00. Berdasarkan uji shapiro-wilk,
diperoleh nilai signifikansi p=0.003, sehingga data tersebut tidak tersebar normal.
Namun, setelah ditransformasi menggunakan Log 10 data pendapatan menjadi
normal (p=0.684). Sebagian besar contoh laki-laki (94.7%) dan perempuan (75%)
tergolong miskin berdasarkan pendapatan/kapita/bulan. Berdasarkan uji Shapiro-
wilk, diperoleh nilai signifikansi p=0.003 (p<0.05), sehingga data tersebut tidak
normal. Median dari besar keluarga adalah 4. Jumlah keluarga yang paling besar
adalah 10 orang dan jumlah keluarga yang paling kecil adalah 2 orang.
Berdasarkan besar keluarga, sebagian besar laki-laki (52.6%) dan
perempuan (68.8%) tergolong ke dalam keluarga kecil (≤4 orang). Berdasarkan uji
Shapiro-wilk, diperoleh nilai signifikansi p=0.003 (p<0.005), sehingga data tersebut
tidak normal. Median dari besar keluarga adalah 4. Jumlah keluarga paling besar
adalah 10 orang dan paling kecil 2 orang.
Gaya Hidup
Gaya hidup contoh meliputi kebiasaan merokok, kebiasaan konsumsi
alkohol, dan kebiasaan olahraga. Tabel 9 menunjukkan data sebaran gaya hidup
contoh berdasarkan kebiasaan merokok, kebiasaan konsumsi alkohol, dan
kebiasaan olahraga.
Tabel 9 Sebaran contoh berdasarkan kebiasaan merokok, kebiasaan konsumsi
alkohol, dan kebiasaan merokok
Gaya hidup Laki-laki Perempuan
n % n %
Kebiasaan merokok
Tidak 5 26.3 12 75
Ya 14 73.7 4 25

16
Tabel 9 Sebaran contoh berdasarkan kebiasaan merokok, kebiasaan konsumsi
alkohol, dan kebiasaan merokok (Lanjutan)
Gaya hidup Laki-laki Perempuan
n % n %
Total 19 100 19 100
Jumlah rokok
Ringan (≤10 batang/hari) 4 28.6 4 100
Sedang (11-20
batang/hari)
8 57.1 0 0
Berat (≥20 batang/hari) 2 14.3 0 0
Total 14 100 4 100
Kebiasaan konsumsi
alkohol
Tidak 11 57.9 15 93.7
Ya 8 42.1 1 6.3
Total 19 100 16 100
Konsumsi alkohol (mL)
0-190 mL 1 12.5 1 100
190 mL 0 0 0 0
>190 mL 7 87.5 0 0
Total 8 100 1 100
Kebiasaan olahraga
Tidak 6 31.6 5 31.3
Ya 13 68.4 11 68.7
Total 19 100 16 100
Frekuensi olahraga
Tidak sering (<3
kali/minggu)
14 73.7 10 62.5
Sering (≥3 kali/minggu) 5 26.3 6 37.5
Total 13 100 11 100
Durasi olahraga
Tidak sering (<30 menit) 8 42.1 8 50
Sering (≥30 menit) 11 57.9 8 50
Total 19 100 16 100
Kebiasaan merokok
Jumlah contoh yang merokok adalah 18 orang (51.4%), dengan median 2.
Sebanyak 14 laki-laki dan 4 perempuan dari 18 orang yang memiliki kebiasaan
merokok. Berdasarkan jumlah rokok yang dihisap dalam sehari, terdapat 4 laki-laki
(28.6%) dan 4 perempuan (100%) yang dikategorikan sebagai perokok ringan (≤10
batang/hari), 8 contoh laki-laki (57.1%) dikategorikan sebagai perokok sedang (11-
20 batang/hari), dan 2 laki-laki (14.3%) yang dikategorikan sebagai perokok berat
(≥20 batang/hari). Kebiasaan merokok contoh dengan jumlah rokok yang paling
sedikit dan paling banyak dihisap dalam sehari adalah 2 batang dan 36 batang.
Berdasarkan uji shapiro-wilk, nilai signifikansi untuk kebiasaan merokok adalah
p=0.000 (p<0.05), sehingga kebiasaan merokok menyebar tidak normal.

17
Kebiasaan konsumsi alkohol Sebagian besar contoh tidak memiliki riwayat konsumsi alkohol, yaitu 11
laki-laki (57.9%) dan 15 perempuan (93.7%), dan yang memiliki riwayat konsumsi
alkohol sebanyak 8 laki-laki (42.1%) dan 1 perempuan (6.3%). Ditinjau dari 9 yang
memiliki riwayat konsumsi alkohol, sebanyak 1 laki-laki (12.5%) dan 1 perempuan
(100%) yang tergolong ke dalam kategori 0-190 mL dan 7 laki-laki(87.5%) yang
tergolong ke dalam kategori >190 mL. Median dari jumlah alkohol adalah 0.
Jumlah (mL) alkohol yang paling sedikit dan paling banyak dikonsumsi oleh contoh
adalah 65 mL dan 700 mL/minggu. Berdasarkan uji shapiro-wilk, nilai sgnifikansi
kebiasaan konsumsi alkohol adalah p=0.000 (p<0.05), sehingga kebiasaan
konsumsi alkohol contoh tidak menyebar normal.
Kebiasaan olahraga
Sebagian besar contoh, yaitu 13 laki-laki (68.4%) dan 11 perempuan
(68.7%) terbiasa olahraga, serta 6 laki-laki (31.6%) dan 5 perempuan (31.3%) tidak
terbiasa olahraga. Ditinjau dari frekuensi olahraga, sebagian besar contoh tergolong
ke dalam kategori tidak sering melakukan olahraga (<3 kali/minggu), yaitu 14 laki-
laki (73.7%) dan 10 perempuan (62.5%). Ditinjau dari durasi olahraga, sebagian
besar contoh tergolong sering melakukan olahraga (≥30 menit), yaitu 11 laki-laki
(57.9%) dan 8 perempuan (50%). Median dari durasi olahraga adalah 30. Durasi
paling rendah dan paling tinggi dalam setiap kali melakukan olahraga adalah 5
menit dan 120 menit. Jenis olahraga yang dilakukan oleh setiap contoh berbeda-
beda. Jenis olahraga yang dilakukan contoh meliputi, aerobik, jogging, bermain
voli, bersepeda statis, dan bermain golf.
Kebiasaan Makan
Kebiasaan makan adalah cara individu memilih pangan apa yang
dikonsumsi sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis, psikologi, dan sosial
budaya (Suhardjo 1989). Kebiasaan makan contoh meliputi kebiasaan konsumsi
makanan asin, tinggi, lemak, dan bumbu, kebiasaan konsumsi air, kebiasaan
konsumsi minuman berenergi, dan kebiasaan konsumsi suplemen.
Konsumsi Makanan Sehat
Konsumsi makanan sehat terdiri atas beberapa jenis golongan makanan,
diantaranya golongan makanan pokok, golongan lauk pauk, golongan sayuran,
golongan buah-buahan, serta golongan susu dan hasil olahannya. Pada setiap
golongannya akan diurutkan bahan makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh
contoh, persentase yang mengonsumsi, frekuensi rata-rata/minggu, dan median
(min-maks). Golongan makanan pokok meliputi nasi (beras putih), nasi merah, nasi
hitam, bihun, kentang, makaroni, mie kering, mie basah, roti putih, singkong, ubi,
sereal, dan lainnya. Golongan lauk pauk meliputi tempe, tahu, ayam, telur, ikan
segar, daging sapi, daging kambing, daging bebek, dan lainnya. Golongan sayuran
meliputi bayam, buncis, brokoli, daun singkong, jagung muda, jantung pisang,
kacang panjang, kembang kol, labu siam, nangka muda, pare, pepaya muda, sawi,
tauge, sayur asem, kangkung, wortel, sayur sup, dan lainnya. Golongan buah
meliputi apel, jambu, jeruk, mangga, melon, pepaya, pisang, semangka, jus buah,
dan lainnya. Golongan susu dan hasil olahannya meliputi susu segar, susu bubuk,
dan yoghurt. Tabel 10 menunjukkan frekuensi konsumsi 5 pangan dari masing-
masing kelompok pangan.

18
Tabel 10 Frekuensi dan perkiraan konsumsi 5 jenis pangan yang paling banyak dikonsumsi
No. Jenis makanan % Frekuensi
konsumsi/mgg
(kali)
Median (min-maks) Jenis makanan % Frekuensi
konsumsi/mgg
(kali)
Median (min-
maks)
1 Makanan pokok:
a. Nasi (beras
putih)
b. Kentang
c. Roti putih
d. Singkong
e. Bihun
100
78.9
78.9
73.7
57.9
20.1±5.6
1±1
3.1±4.1
2.2±3.9
0.6±0.7
2818.4 (700-4200)
183.1 (140-1470)
46.2 (30-420)
331.6 (330-945)
25.8 (20-100)
Nasi (beras
putih)
Bihun
Kentang
Roti putih
Singkong
100
87.5
81.3
68.8
62.5
18±3.8
1.9±2.4
2±2.1
2.2±2.9
0.8±0.9
2800 (700-2800)
110.1 (105-350)
251.3 (140-1050)
44.4 (40-210)
93.5 (100-700)
2 Lauk pauk
a. Telur
b. Tempe
c. Tahu
d. Daging sapi
e. Ayam
100
94.7
94.7
94.7
94.7
8.7±4.3
5.7±4.5
5.4±4.5
2.7±3
3.5±3.8
590.5 (385-1925)
132.9 (130-600)
275.9 (210-770)
89.6 (35-150)
177.9 (150-210)
Tahu
Daging sapi
Ikan segar
Telur
Tempe
100
100
100
93.8
93.8
6.7±7.1
1.7±2
2.2±2.5
4.5±6.4
6.2±7.3
347 (347-770)
54.6 (35-70)
82.4 (20-120)
232.7 (200-1925)
147.4 (75-350)
3 Sayuran
a. Sayur sup
b. D.Singkong
c. Bayam
d. Sayur asem
e. Wortel
63.2
57.9
52.6
52.6
52.6
1.3±1.3
2.1±2.4
1.1±1.8
1±1.2
1.2±1.8
98.2 (30-100)
127.7 (50-150)
54.6 (50-100)
64.5 (50-100)
60.2 (10-70)
Sayur sup
D.Singkong
Sayur asem
Sawi
Bayam
68.8
68.8
68.8
68.8
62.5
0.7±0.7
0.9±1
0.8±1.1
1.2±1.9
0.6±0.6
55.2 (50-100)
66.9 (50-100)
49 (50-100)
79.3 (30-100)
31.1 (50-100)

19
Tabel 10 Frekuensi dan perkiraan konsumsi 5 jenis pangan yang paling banyak dikonsumsi (Lanjutan)
No. Jenis makanan % Frekuensi
konsumsi/mgg
(kali)
Median (min-maks) Jenis makanan % Frekuensi
konsumsi/mgg
(kali)
Median (min-
maks)
4 Buah
a. Pepaya
b. Jeruk
c. Pisang
d. Semangka
e. Apel
78.9
63.2
63.2
63.2
52.6
2.5±2.9
1.9±2.7
1.8±2.7
2.3±3
1.1±1.9
262 (150-660)
96.4 (30-110)
112.6 (25-200)
274.8 (180-900)
90.8 (43-170)
Pisang
Semangka
Pepaya
Jeruk
Apel
75
50
43.8
43.8
43.8
2.5±3.2
1±2
1.8±3
1.2±2.1
1.7±2.7
145.4 (125-350)
157.8 (88-180)
221.8 (50-550)
59.1 (30-110)
130.9 (22-255)
5 Susu dan hasil
olahannya
a. Susu bubuk
b. Susu segar
31.6
21.1
1±3.4
1.4±2.8
179.3 (125-250)
255.4 (125-500)
Susu bubuk
Susu segar
50
12.5
0.5±1.9
3.2±4.6
99.6 (100-250)
606.4 (100-500)
6 Makanan asin
dan awetan
a. Sarden
b. Ikan asin
c. Nugget
d. Kerupuk
e. Sosis
89.5
57.9
57.9
52.6
52.6
1.5±2.3
1.9±5.1
0.4±0.6
2.4±3.3
0.4±0.5
51.6 (20-120)
434 (75-350)
15.6 (15-40)
36.1 (10-40)
15.6 (10-50)
Ikan asin
Sarden
Nugget
Keju
Sosis
87.5
75
75
68.8
62.5
3.2±3.3
0.6±0.8
1.5±2.6
1.7±2.5
0.9±1.2
77.2 (15-120)
23.6 (20-40)
71.6 (10-90)
43.9 (10-80)
51.8 (10-120)

20
Tabel 10 Frekuensi dan perkiraan konsumsi 5 jenis pangan yang paling banyak dikonsumsi (Lanjutan)
No. Jenis makanan % Frekuensi
konsumsi/mgg
(kali)
Median (min-maks) Jenis makanan % Frekuensi
konsumsi/mgg
(kali)
Median (min-
maks)
7 Makanan sumber
lemak
a. Telur ayam
b. Daging ayam
dengan kulit
c. Gorengan
d. Daging sapi
e. Udang
100
94.7
89.5
78.9
73.7
8±4.4
3.4±3.8
3.4±3.3
2.3±2.9
1.7±3.6
603.7 (55-1540)
175.3 (40-240)
603.6 (120-840)
74.5 (35-140)
71.2 (20-140)
Telur ayam
Daging ayam
dengan kulit
Gorengan
Daging sapi
Udang
93.8
87.5
87.5
81.3
75
4.7±6.3
2.4±2.3
7.3±7.3
1.6±2
0.6±0.6
240.4 (55-330)
119.7 (80-420)
750.6 (120-2100)
52.3 (35-70)
28.6 (20-35)
8 Bumbu
a. Kecap manis
b. Garam
c. Saus tomat
d. Kecap asin
57.9
42.1
21.1
10.5
5.1±5.6
3.9±5.8
1.6±3.1
0.8±2.4
44.2 (10-50)
18.4 (5-20)
9.2 (10-20)
5.5 (10-30)
Garam
Kecap manis
Saus tomat
Kecap asin
56.3
43.8
31.3
12.5
5.5±6.6
5±7.8
4±6.9
1.5±5.8
25.7 (5-30)
42 (10-60)
51.3 (10-60)
14 (10-30)

21
Jenis makanan pokok yang paling sering dikonsumsi oleh contoh laki-laki
adalah nasi (beras putih), kentang, roti putih, singkong, dan bihun, dengan frekuensi
konsumsi paling besar dan paling kecil adalah nasi (beras putih) dan bihun. Pada
contoh perempuan, jenis makanan pokok yang paling sering dikonsumsi adalah nasi
(beras putih), bihun, kentang, roti putih, dan singkong, dengan frekuensi konsumsi
paling besar dan paling kecil adalah nasi (beras putih) dan bihun. Jenis lauk pauk
yang paling sering dikonsumsi oleh contoh laki-laki adalah telur, tempe, tahu,
daging sapi, dan ayam, dengan frekuensi konsumsi paling besar dan paling kecil
adalah telur dan daging sapi. Pada contoh perempuan, jenis lauk pauk yang paling
sering dikonsumsi adalah tahu, daging sapi, ikan segar, telur, dan tempe, dengan
frekuensi konsumsi paling besar dan paling kecil adalah tahu dan daging sapi.
Jenis sayuran yang paling sering dikonsumsi oleh contoh laki-laki adalah
sayur sup, daun singkong, bayam, sayur asem, dan wortel, dengan frekuensi
konsumsi paling besar dan paling kecil adalah sayur sup dan sayur asem. Pada
contoh perempuan jenis sayuran yang paling sering dikonsumsi adalah sayur sup,
daun singkong, sayur asem, sawi, dan bayam, dengan frekuensi konsumsi paling
besar dan paling kecil adalah sawi dan bayam. Jenis buah yang paling sering
dikonsumsi oleh contoh laki-laki adalah pepaya, jeruk, pisang, semangka, dan apel,
dengan frekuensi konsumsi paling besar dan paling kecil adalah pepaya dan apel.
Pada contoh perempuan, jenis buah yang paling sering dikonsumsi adalah pisang,
semangka, pepaya, jeruk, dan apel, dengan frekuensi konsumsi paling besar dan
paling kecil adalah pisang dan semangka. Jenis susu dan hasil olahannya yang
paling sering dikonsumsi oleh contoh laki-laki dan perempuan adalah susu bubuk
dan susu segar, dengan frekuensi konsumsi paling besar dan paling kecil adalah
susu segar dan susu bubuk.
Konsumsi makanan asin dan awetan
Konsumsi makanan asin dan awetan terdiri atas beberapa jenis bahan
makanan, diantaranya ikan asin, rusip, kerupuk, keripik asin, keju mie instan, sosis,
nugget, sarden, kacang telur bungkus, dan kacang kulit bungkus. Pada setiap
jenisnya akan diurutkan bahan makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh
contoh, persentase yang mengonsumsi, frekuensi rata-rata/minggu, dan median
(min-maks) (Tabel 10). Jenis makanan asin dan awetan yang paling sering
dikonsumsi oleh contoh laki-laki adalah sarden, ikan asin, nugget, kerupuk, dan
sosis, dengan frekuensi konsumsi paling besar dan paling kecil adalah kerupuk dan
sosis. Pada contoh perempuan, jenis makanan asin dan awetan yang paling sering
dikonsumsi adalah ikan asin, sarden, nugget, keju, dan sosis, dengan frekuensi
konsumsi paling besar dan paling kecil adalah ikan asin dan sarden.
Konsumsi makanan sumber lemak
Konsumsi makanan sumber lemak terdiri atas beberapa jenis bahan
makanan, diantaranya telur ayam, gorengan, daging ayam dengan kulit, susu full
krim, daging sapi, jeroan, daging kambing, gajih, udang, kepiting, kerang, santan,
dan mentega. Pada setiap jenisnya akan diurutkan bahan makanan yang paling
banyak dikonsumsi oleh contoh, persentase yang mengonsumsi, frekuensi rata-
rata/minggu, dan median (min-maks) (Tabel 10). Jenis makanan sumber lemak
yang paling sering dikonsumsi oleh contoh laki-laki adalah telur ayam, daging
ayam dengan kulit, gorengan, daging sapi, dan udang, dengan frekuensi konsumsi
paling besar dan paling kecil adalah telur ayam dan udang. Pada contoh perempuan,

22
jenis makanan sumber lemak yang paling sering dikonsumsi adalah telur ayam,
daging ayam dengan kulit, gorengan, daging sapi, dan udang, dengan frekuensi
konsumsi paling besar dan paling kecil adalah gorengan dan udang.
Konsumsi bumbu dan gula
Konsumsi bumbu terdiri atas beberapa jenis bumbu, diantaranya kecap
manis, garam, saus tomat/sambal, dan kecap asin. Pada setiap jenisnya akan
diurutkan jenis bumbu yang paling banyak dikonsumsi oleh contoh, persentase
yang mengonsumsi, frekuensi rata-rata/minggu, dan median (min-maks) (Tabel
10). Jenis bumbu yang paling sering dikonsumsi oleh contoh laki-laki adalah kecap
manis, garam, saus tomat, dan kecap asin, dengan frekuensi konsumsi paling besar
dan paling kecil adalah kecap manis dan kecap asin. Pada contoh perempuan jenis
bumbu yang paling sering dikonsumsi adalah garam, kecap manis, saus tomat, dan
kecap asin, dengan frekuensi konsumsi paling besar dan paling kecil adalah garam
dan kecap asin. Konsumsi gula juga diteliti pada penelitian ini. Konsumsi gula
diperoleh dengan menanyakan konsumsi teh manis dan penambahan gula yang
ditambahkan. Rata-rata contoh minum teh manis menggunakan 3 sdm dengan
perkiraan berat 38 gram/hari. Konsumsi gula yang terlalu tinggi akan membuat
glukosa darah meningkat dan membuat kerja insulin ekstra. Konsumsi gula yang
terlalu tinggi dalam jangka waktu terus – menerus akan berdampak terhadap
kejadian diabetes mellitus.
Konsumsi air putih
Konsumsi air putih yang dianjurkan dalam sehari adalah ≥8 gelas/hari atau
setara dengan 2000 mL. Konsumsi air putih ≥8 gelas/hari dikatakan cukup,
sebaliknya jika konsumsi air putih <8 gelas/hari dikatakan tidak cukup. Tabel 11
merupakan sebaran data kebiasaan konsumsi air putih contoh.
Tabel 11 Sebaran contoh berdasarkan kebiasaan konsumsi air putih
Kebiasaan konsumsi air
putih
Laki-laki Perempuan
n % n %
Tidak cukup (<8 gelas
atau <2000 mL)
14 73.7 11 68.8
Cukup (≥8 gelas atau
≥2000 mL)
5 26.3 5 31.2
Total 19 100 16 100
Sebagian besar contoh sebanyak 14 laki-laki (73.7%) dan 11 perempuan
(68.8%) tergolong tidak cukup dalam mengonsumsi air putih, serta sebanyak 5 laki-
laki (26.3%) dan 5 perempuan (31.2%) tergolong cukup dalam mengonsumsi air
putih. Median dari kebiasaan konsumsi air putih adalah 600. Jumlah (mL) air putih
yang paling sedikit dikonsumsi oleh contoh adalah 100 mL dan yang paling banyak
adalah 3000 mL.

23
Konsumsi minuman berenergi
Minuman energi adalah jenis minuman yang ditujukan untuk menambah
energi seseorang yang meminumnya (Paddock 2008). Tabel 12 menunjukkan
sebaran kebiasaan konsumsi minuman bernergi contoh.
Tabel 12 Sebaran contoh berdasarkan kebiasaan konsumsi minuman berenergi
konsumsi
minuman
berenergi
Laki-laki Perempuan
n % n %
Tidak 6 31.6 11 68.8
Ya 13 68.4 5 31.2
Total 19 100 16 100
Jumlah minuman berenergi
0.1-1.3 mL 0 0 1 20
1.3-450 mL 9 69.2 3 60
>450 mL 4 30.8 1 20
Total 13 100 5 100
Sebanyak 6 laki-laki (31.6%) dan 11 perempuan (68.8%) tidak
mengonsumsi minuman berenergi, serta sebanyak 13 laki-laki (68.4%) dan 5
perempuan (31.2%) memiliki kebiasaan mengonsumsi minuman berenergi.
Ditinjau dari banyaknya minuman berenergi yang dikonsumsi (mL), terdapat 1
perempuan (20%) yang termasuk ke dalam kategori 0.1-1.3 mL, 9 laki-laki (69.2%)
dan 3 perempuan (60%) yang termasuk ke dalam kategori 1.3-450 mL, serta 4 laki-
laki (30.8%) dan 1 perempuan (205) yang termasuk ke dalam kategori >450 mL.
Volume minuman berenergi (mL) yang paling tinggi dikonsumsi adalah 1800 mL
dan yang paling rendah dikonsumsi adalah 10 mL. Jenis minuman berenergi yang
dikonsumsi contoh adalah extrajoss, kratindaeng, dan kukubima energi.
Konsumsi suplemen
Suplemen makanan adalah produk yang digunakan untuk melengkapi
makanan, mengandung satu atau lebih bahan, seperti vitamin, mineral, tumbuhan
atau bahan yang berasal dari tumbuhan, asam amino, bahan yang digunakan untuk
meningkatkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) atau konsentrat, metabolit,
konstituen, ekstrak atau kombinasi dari beberapa dari bahan di atas. Suplemen
makanan dapat berupa produk padat meliputi, tablet, tablet hisap, tablet kunyah,
serbuk, kapsul, kapsul lunak, granula, pastiles, atau produk cari berupa tetes, sirup,
atau larutan (BPOM 2004). Tabel 13 menunjukkan sebaran kebiasaan konsumsi
suplemen contoh.

24
Tabel 13 Sebaran contoh berdasarkan kebiasaan konsumsi suplemen
Konsumsi
suplemen
Laki-laki Perempuan
n % n %
Tidak 12 63.2 6 37.5
Ya 7 36.8 10 62.5
Total 19 100 16 100
Frekuensi
konsumsi
0.1-1.3 4 57.1 3 30
1.3 0 0 0 0
>1.3 3 42.9 7 70
Total 7 100 10 100
Sebanyak 12 laki-laki (63.2%) dan 6 perempuan (37.5%) tidak memiliki
kebiasaan mengonsumsi suplemen, serta terdapat 7 laki-laki (36.8%) dan 10
perempuan (62.5%) memiliki kebiasaan mengonsumsi suplemen. Frekuensi
konsumsi suplemen dibedakan menjadi 3 kategori berdasarkan sebaran data, yaitu
0.1-1.3, 1.3, dan >1.3. Sebanyak 4 laki-laki (57.1%) dan 3 perempuan (30%)
termasuk ke dalam kategori 0.1-1.3, serta 3 laki-laki (42.9%) dan 7 perempuan
(70%) termasuk ke dalam kategori >3. Frekuensi konsumsi suplemen tertinggi
adalah 3 kali/hari dan frekuensi konsumsi suplemen terendah adalah 1 kali/hari.
Jenis suplemen yang dikonsumsi oleh contoh adalah neurobion, herbal life
(susu+obat+es), pil pelangsing, vitamin A, teh pelangsing, vitamin B12, hamaviton,
sangobion, neurobion, supradin, vitamin C, centrum, dan vitamin C. Sebagian besar
contoh mengonsumsi suplemen 1 serving size (1 tablet, 1 kapsul, botol, dan gelas)
Penyakit Lain yang Berhubungan
Penyakit lain yang berhubungan adalah keberadaan penyakit yang diderita
oleh contoh selain penyakit chronic kidney disease (CKD), seperti hipertensi,
diabetes mellitus, atau kombinasinya. Tabel 14 menunjukkan sebaran riwayat
kesehatan contoh.
Tabel 14 Sebaran contoh berdasarkan riwayat kesehatan
Riwayat
Kesehatan
Laki-laki Perempuan
n % n %
Penyakit lain
selain CKD
Tidak ada 3 15.8 2 12.5
Ada 16 84.2 14 87.5
Total 19 100 16 100
Jenis penyakit
lain
Hipertensi 9 56.3 7 50

25
Tabel 14 Sebaran contoh berdasarkan riwayat kesehatan (Lanjutan)
Riwayat
Kesehatan
Laki-laki Perempuan
n % n %
Diabetes mellitus 4 25 2 14.3
Hipertensi dan
diabetes mellitus
3 18.7 5 35.7
Total 16 100 14 100
Riwayat CKD
Keluarga
Tidak ada 0 0 3 18.8
Ada 19 100 13 81.2
Total 19 100 16 100
Riwayat selain
CKD keluarga
Tidak ada 10 52.6 8 50
Ada 9 47.4 8 60
Total 19 100 16 100
Sebagian besar contoh memiliki penyakit lain selain CKD, yaitu 16 laki-
laki (84.2%) dan 14 perempuan (87.5%). Penyakit lain selain CKD yang dimiliki
oleh contoh adalah hipertensi, diabetes mellitus, dan kombinasi keduanya.
Sebanyak 9 laki-laki (56.3%) dan 7 perempuan (50%) memiliki riwayat hipertensi,
4 laki-laki (25%) dan 2 perempuan (14.3%) memiliki riwayat diebetes mellitus,
serta 3 laki-laki (18.7%) dan 5 perempuan (35.7%) memiliki riwayat penyakit
hipertensi dan diabetes mellitus. Selain penyakit hipertensi, diabetes mellitus, dan
kombinasi keduanya, sebagian contoh juga memiliki riwayat penyakit jantung
koroner, katarak, dan stroke.
Riwayat penyakit chronic kidney disease merupakan penyakit yang dapat
diturunkan dari orang tua. Sebanyak 19 laki-laki (100%) dan 13 perempuan (81.2%)
memiliki riwayat penyakit CKD dari orang tuanya, yaitu ibu. Sebanyak 9 laki-laki
(47.4%) dan 8 perempuan (50%) memiliki riwayat penyakit lain selain CKD dari
orang tuanya. Penyakit tersebut adalah hipertensi, diabetes mellitus, dan jantung
koroner.
Status Gizi
Status gizi merupakan keadaan kesehatan tubuh seseorang atau sekelompok
orang yang diakibatkan oleh konsumsi, penyerapan (absorbsi), dan pemanfaatan
(utilization) zat gizi makanan. Penilaian terhadap status gizi seseorang atau
sekelompok orang akan menentukan apakah orang atau sekelompok orang tersebut
memiliki status gizi yang baik atau tidak (Riyadi 2001). Penilaian status gizi secara
langsung dapat dibagi menjadi empat, yaitu antropometri, klinis, biokimia, dan
biofisik.
Penilaian antropometri untuk menilai status gizi yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah indeks massa tubuh (IMT). IMT mengindikasikan berat tubuh

26
terhadap tinggi tubuh seseorang. IMT digunakan sebagai suatu ukuran untuk
menentukan status kegemukan dan obesitas. Kelebihan pengukuran IMT adalah
mudah, cepat, dan tidak bersifat invasif (Gibson 2005). Tabel 15 menunjukkan
sebaran indeks masa tubuh (IMT) contoh.
Table 15 Sebaran contoh berdasarkan Indeks masa tubuh (IMT) contoh
Status Gizi Laki-laki Perempuan
n % n %
Underweight 3 15.8 5 31.6
Normal 7 36.8 3 18.8
Overweight 4 21.1 3 18.8
Obese I 3 15.8 3 18.8
Obese II 2 10.5 2 12.5
Total 19 100 16 100
Sebagian besar contoh, baik laki-laki maupun perempuan memiliki status
gizi lebih (overweight dan obese), yaitu 47.4% laki-laki dan 50.1%. Sisanya adalah
underweight sebanyak 15.8% laki-laki dan 31.6% perempuan, dan normal sebanyak
36.8% laki-laki dan 18.8% perempuan.
Hubungan antar Variabel
Hubungan usia dan konsumsi suplemen
Data usia menyebar normal karena memiliki p>0.05 (p=0.404) dan data
konsumsi suplemen tidak menyebar normal p<0.05 (p=0.000), sehingga uji korelasi
yang digunakan adalah uji korelasi Spearman. Hasil uji korelasi Spearman
menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan (p<0.05) antara usia dan konsumsi
suplemen (p=0.042, r=-0.346), serta usia dan frekuensi konsumsi suplemen
(p=0.017, r=-0.402). Nilai korelasi negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi usia
maka konsumsi dan frekuensi suplemen semakin sedikit, sebaliknya semakin
rendah usia maka konsumsi dan frekuensi suplemen semakin tinggi. Hal ini tidak
sejalan dengan penelitian Dickinson dan MacKay (2014) yang menyatakan bahwa
semakin meningkatnya usia, prevalensi dan frekuensi penggunaan suplemen
meningkat pada laki – laki dari 36% - 66% dan pada perempuan dari 43% - 75%.
Menurut hasil Third National Health and Nutrition Examination Survey
(NHANES III) tahun 1988-1994, suplemen makanan paling banyak digunakan oleh
anak – anak dan dewasa (Koplan et al. 1996), sedangkan menurut Greger (2001)
umur yang lebih tua merupakan karakteristik demografi yang berhubungan dengan
konsumsi suplemen makanan. Semakin tua seseorang semakin menurun fungsi
organ tubuh yang berakibat menurunnya penyerapan zat gizi sehingga diperlukan
suplemen makanan (Sarjono 2010). Messerer et.al (2001) dalam penelitiannya di
Swedia, menyatakan bahwa umur merupakan prediktor yang terbaik dalam
penelitian mengenai penggunaan suplemen makanan. Menurut Balluz et.al (2000),
rata-rata umur pengguna suplemen makanan di United States adalah 37 tahun.
Penelitian Balluz et.al (2000) juga menunjukkan ada peningkatan konsumsi
suplemen makanan pada mereka yang kelompok umurnya lebih tinggi. Hasil
penelitian di Jepang yang dilakukan Ishiara et.al (2003) menunjukkan bahwa

27
terdapat peningkatan yang signifikan pada kelompok usia yang tertinggi dalam
konsumsi suplemen. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi umur seseorang, maka
kecenderungan untuk mengonsumsi suplemen makanan akan semakin besar.
Hubungan pendidikan dan konsumsi suplemen
Data pendidikan menyebar tidak normal p<0.05 (p=0.000) dan data
konsumsi suplemen tidak menyebar normal, sehingga uji korelasi yang digunakan
adalah uji korelasi Spearman. Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan terdapat
hubungan yang signifikan (p<0.05) antara pendidikan dan konsumsi suplemen
(p=0.018, r=0.398). Nilai korelasi positif menunjukkan bahwa semakin tinggi
pendidikan maka konsumsi suplemen semakin tinggi. Hal ini diduga semakin tinggi
pendidikan seseorang, maka pengetahuannya pun akan semakin meningkat.
Pengetahuan yang tinggi akan berdampak terhadap kepedulian terhadap kesehatan
yang tinggi pula. Tingkat kepedulian terhadap kesehatan ditunjukkan dengan
konsumsi suplemen.
Hasil penelitian ini sejalan dengan Vatanparast (2010) yang menyatakan
bahwa orang-orang yang tamat SMA memiliki kesempatan 1.4 kali lebih besar
untuk mengonsumsi suplemen dibandingkan dengan orang-orang yang tidak tamat
SMA. Berdasarkan NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey)
penggunaaan suplemen lebih tinggi pada orang yang berpendidikan dibandingkan
dengan orang yang tidak berpendidikan. Pada NHANES (National Health and
Nutrition Examination Survey) tahun 1999-2000 dilaporkan bahwa konsumsi
suplemen sebanyak 62% pada orang-orang yang pendidikannya lebih dari SMA,
48% pada orang-orang yang tamat SMA, dan 35% pada orang-orang yang tidak
tamat SMA (Bailey 2011). Sedangkan pada NHANES ((National Health and
Nutrition Examination Survey) tahun 2003-2006 dilaporkan bahwa sebanyak 61%
orang dengan pendidikan tinggi mengonsumsi suplemen dan hanya 37% pada orang
dengan pendidikan rendah (Radimer 2004).
Hubungan antara nilai GFR (CKD) dan gaya hidup
Kebiasaan Merokok
Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan tidak terdapat hubungan yang
signifikan antara nilai GFR (CKD) dan kebiasaan merokok (p=0.560), serta
hubungan antara nilai GFR (CKD) dan jumlah batang rokok (p=0.269). Hal ini
tidak sejalan dengan penelitian Bleyer (2000), yang menyatakan terdapat hubungan
yang signifikan antara kebiasaan merokok dengan peningkatan serum kreatinin atau
dengan kata lain penurunan nilai GFR. Pada hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa kebiasaan merokok akan meningkatkan serum kreatinin 5 kali lipat
dibandingkan dengan tidak merokok, jika dalam sehari menghisap rokok ≥20
batang rokok. Sebuah meta analisis dari 17 penelitian atau kajian case control
menemukan bahwa kejadian gagal ginjal kronis (CKD) berhubungan signifikan
dengan kebiasaan merokok ≥20 batang/hari (OR:1.51, 95% CI 1.06 – 2.15) dan
merokok >40 tahun (OR:1.45, 95% CI 1.00-2.09) (Jones-Burton 2007).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang
signifikan antara nilai GFR (CKD) dan kebiasaan merokok (p>0.05). Hal ini diduga
karena sebaran data kebiasaan merokok pada contoh tidak menyebar normal.
Sebanyak 51.4% contoh yang memiliki kebiasaan merokok dan rata-rata jumlah
batang rokok yang dihisap adalah 6 batang/hari. Hanya terdapat 2 contoh yang
memiliki kebiasaan merokok ≥20 batang/hari, yaitu 24 batang dan 36 batang.

28
Sementara menurut penelitian Bleyer (2000) dan (Jones-Burton 2007), kebiasaan
merokok akan mempengaruhi nilai GFR (CKD) paling tidak memiliki kebiasaan
merokok ≥20 batang rokok/hari.
Menurut Grassi (1994) dan Orth (2000), Efek merokok yaitu meningkatkan
pacuan simpatis yang akan berakibat pada peningkatan tekanan darah, takikardi,
dan penumpukan katekolamin dalam sirkulasi. Pada fase akut beberapa pembuluh
darah juga sering mengalami vasokonstriksi misalnya pada pembuluh darah
koroner, sehingga pada perokok akut sering diikuti dengan peningkatan tahanan
pembuluh darah ginjal sehingga terjadi penurunan laju filtrasi glomerulus dan fraksi
filter.
Konsumsi Alkohol
Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan tidak terdapat hubungan yang
signifikan antara nilai GFR (CKD) dan kebiasaan konsumsi alkohol ) (p=0.123),
serta hubungan antara nilai GFR (CKD) dan volume alkohol (p=0.134). Kebiasaan
konsumsi alkohol dihubungkan dengan kejadian hipertensi. Oleh karena itu, secara
tidak langsung mengarah pada kejadian gagal ginjal kronis (CKD) (Parekh 2001).
Banyak penelitian yang menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara
kebiasaan konsumsi alkohol dan nilai GFR (CKD). Akan tetapi, ada juga penelitian
yang gagal menunjukkan hubungan antara kebiasaan konsumsi alkohol dan nilai
GFR (CKD). Hasil penelitian Shankar (2006), menunjukkan tidak terdapat
hubungan yang signifikan antara kebiasaan konsumsi alkohol dengan kejadian
gagal ginjal kronis apabila konsumsi alkohol <4 serving size/hari. Pada penelitian
cross sectional dan analisis longitudinal menunjukkan bahwa terdapat hubungan
yang signifikan antara nilai GFR (CKD) dan konsumsi alkohol ≥4 serving size/hari
(Perneger 1999).
Sebaran kebiasaan konsumsi alkohol contoh tidak menyebar normal.
Sebanyak 9 contoh (25.7%) yang memiliki kebiasaan konsumsi alkohol dan sisanya
tidak memiliki riwayat konsumsi alkohol. Menurut Shanker (2006), konsumsi
alkohol ≥4 serving size/hari memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian
gagal ginjal kronis. Tidak ada satupun contoh yang memiliki kebiasaan konsumsi
alkohol ≥4 serving size/hari. Hanya terdapat 2 contoh yang mengonsumsi 3 serving
size/minggu. Oleh karena itu, hal ini diduga menjadi faktor yang menyebabkan
hubungan antara kebiasaan konsumsi alkohol tidak berhubungan signifikan
(p>0.05) dengan nilai GFR (CKD).
Pengaruh alkohol dengan kejadian gagal ginjal kronis adalah dengan cara
merespon sistem saraf pusat (hipotalamus) untuk meningkatkan osmolaritas
plasma. Peningkatan osmolaritas plasma diikuti dengan peningkatan sekresi
hormon ADH. Hormon ADH akan menghambat pengeluaran urin, sehingga urin
diserap kembali oleh tubulus dan menjadi racun bagi tubuh. Penumpukan urin di
dalam tubuh mengakibatkan zat sisa metabolisme tidak dapat dibuang (serum
kreatinin dan ureum menumpuk), sehingga menjadi penyebab terhadap kejadian
gagal ginjal kronis (Stump 2004).
Kebiasaan Olahraga
Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan tidak terdapat hubungan yang
nyata (p<0.05) antara nilai GFR (CKD) dan kebiasaan olahraga (p=0.453),
hubungan antara nilai GFR (CKD) dan frekuensi olahraga (p=0.878), serta
hubungan antara nilai GFR (CKD) dan durasi olahraga (p=0.079). Edemack (1997)

29
melakukan penelitian secara acak kepada 30 pasien CKD stage 3-5 untuk melihat
pengaruh olahraga (bersepeda selama 30 menit) terhadap penurunan nilai GFR.
Pasien dibedakan menjadi 2 kelompok, kelompok uji (melakukan olahraga) dan
kontrol (tidak melakukan olahraga). Hasilnya menunjukkan tidak terdapat
perbedaan antara nilai GFR pada kedua kelompok pasien. Olahraga yang dilakukan
rutin 3 kali/minggu dengan durasi ≥30 menit akan memperbaiki nilai tekanan darah
dan denyut jantung (Maria & Johnson 2012), sehingga akan membuat sirkulasi
darah ke ginjal lancar. Menurut Maria & Johnson (2012), faktor yang
mempengaruhi tidak terdapat hubungan antara olahraga dengan nilai GFR adalah
jumlah sampel yang terlalu sedikit, homoginitas subjek, dan kekuatan statistik yang
lemah. Pada penelitian ini juga diduga penyebab tidak ada hubungan antara
kebiasaan olahraga dengan nilai GFR adalah sebaran data kebiasaan olahraga yang
tidak normal, sampel hanya 35 orang (kecil), dan contoh homogen (semua contoh
tergolong ke dalam CKD stage V).
Hubungan antara nilai GFR (CKD) dan kebiasaan makan
Makanan asin dan awetan
Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan tidak terdapat hubungan yang
signifikan antara nilai GFR (CKD) dan kebiasaan konsumsi makanan asin dan
awetan (p=0.358, r=-0.160). Kebiasaan konsumsi makanan asin dan awetan akan
menyebabkan hipertensi, kemudian setelah hipertensi terjadi dalam jangka waktu
yang lama akan menyebabkan gagal ginjal kronis (Stump 2004). Penelitian yang
dilakukan oleh Wang et.al (2014), menyebutkan bahwa konsumsi makanan yang
mengandung garam tinggi secara signifikan berhubungan dengan kejadian
hipertensi (p=0.0003). Hanum (2014) menyebutkan bahwa contoh yang sering
mengonsumsi makanan asin dan awetan memiliki peluang 10 kali lipat mengalami
hipertensi dibandingkan dengan contoh yang tidak mengonsumsi makanan asin dan
awetan (OR;10.035, 95% CI 1.213-82.981). Pada penelitian ini tidak dihubungkan
antara kebiasaan konsumsi makanan asin terhadap kejadian hipertensi. Akan tetapi,
kejadian hipertensi berhubungan signifikan dengan kejadian gagal ginjal kronis
(p<0.05).
Makanan berlemak
Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan tidak terdapat hubungan yang
signifikan antara nilai GFR (CKD) dan kebiasaan konsumsi makanan berlemak
(p=0.987, r=-0.003). Sama halnya dengan kebiasaan konsumsi makanan asin dan
awetan. Kebiasaan konsumsi makanan berlemak akan berhubungan terlebih dahulu
dengan obesitas (IMT) (Stump 2004). Kemudian obesitas (IMT) akan berhubungan
dengan hipertensi dan diabetes mellitus. Hipertensi dan diabetes mellitus
merupakan risiko terhadap kejadian gagal ginjal kronis (p<0.05). Penelitian yang
dilakukan oleh Castillon et.al (2007) di Spanyol menunjukkan bahwa makanan
berlemak berhubungan dengan obesitas 1.26 (95% CI 1.09:1.45, P<0.001) pada pria
dan 1.25 (95% CI 1.11:1.41, P<0.001) pada wanita, dan obesitas sentral 1.17 (95%
CI 1.02:1.34, P<0.001) pada pria dan 1.27 (95% CI 1.13:1.42, P<0.001) pada
wanita. Makanan tinggi lemak atau yang diolah dengan cara digoreng berhubungan
positif dengan kejadian obesitas umum dan sentral. Status gizi berlebih kemudian
akan berpengaruh terhadap penyakit gagal ginjal kronis. Pada penelitian ini, status
gizi (IMT) memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian gagal ginjal kronis
(p<0.05).

30
Bumbu
Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan tidak terdapat hubungan yang
signifikan antara nilai GFR (CKD) dan kebiasaan konsumsi bumbu (p=0.313, r=-
0.176). Hal ini sejalan dengan Stump (2004), penggunaan bumbu (garam, kecap,
saus, dan vetsin) yang semakin sering atau berlebih akan meningkatkan kejadian
hipertensi. Kejadian hipertensi dalam jangka waktu yang lama (kronis) akan
berhubungan dengan kejadian gagal ginjal kronis. Pada penelitian ini tidak
dihubungkan antara kebiasaan konsumsi bumbu dengan kejadian hipertensi.
Berdasarkan riwayat kesehatan contoh telah didapatkan prevalensi penyakit
hipertensi pada contoh. Pada penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan
antara kejadian hipertensi dan penyakit gagal ginjal kronis (p<0.05).
Gula
Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan tidak terdapat hubungan yang
signifikan antara nilai GFR (CKD) dan kebiasaan konsumsi gula (p>0.05, r=-
0.176). Konsumsi gula dihubungkan dengan kejadian diabetes mellitus. Kejadian
diabetes mellitus kronis akan berdampak terhadap gagal ginjal kronis. Menurut
Stump (2004), kadar gukosa darah yang tinggi akan dikeluarkan melalui ginjal
karena insulin tidak dapat mengontrolnya, sehingga ginjal mengalami hiperfiltrasi
dan dalam jangka waktu lama akan mengakibatkan penyakit gagal ginjal kronis.
Pada penelitian ini tidak terdapat hubungan antara nilai GFR (CKD) dan kebiasaan
konsumsi gula. Menurut Stump (2004), konsumsi gula yang berlebih dalam jangka
waktu lama akan berdampak terhadap diabetes mellitus dan berhubungan dengan
kejadian penyakit gagal ginjal kronis.
Air putih
Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan tidak terdapat hubungan yang
signifikan antara nilai GFR (CKD) dan kebiasaan konsumsi air putih (p=0.226, r=-
0.210). Menurut Maria (2012), terdapat hubungan yang signifikan antara nilai GFR
dan kebiasaan konsumsi air putih. Dalam penelitiannya konsumsi air ≥8 gelas (2-
2.5 L/hari) dapat menurunkan prevalensi gagal ginjal kronis (CKD). Pada penelitian
ini hubungan nilai GFR (CKD) dan kebiasaan konsumsi air putih tidak
berhubungan. Hal ini diduga karena sebaran data kebiasaan konsumsi air putih
contoh tidak menyebar normal, jumlah contoh yang kecil, dan contoh homogen.
Konsumsi air putih yang cukup akan membuat volume darah adekuat, sehingga
tekanan dan sirkulasi darah menuju ke ginjal lancar. Selain itu, air putih membantu
proses filtrasi glomerulus (Stump 2004).
Minuman berenergi
Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan tidak terdapat hubungan yang
signifikan antara nilai GFR (CKD) dan kebiasaan konsumsi minuman berenergi
(p=0.897, r=0.023), serta hubungan antara nilai GFR (CKD) dan volume minuman
berenergi (p=0.613, r=0.088). Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Restu
(2015), yang menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan
konsumsi minuman berenergi dengan penyakit gagal ginjal kronis. Hubungan
konsumsi minuman berenergi dan kejadian gagal ginjal kronis adalah sebagai
berikut. Beberapa psikostimulan (kafein dan amfetamin) yang terdapat pada
minuman berenergi terbukti dapat mempengaruhi ginjal. Amfetamin dapat
mempersempit pembuluh darah arteri ke ginjal sehingga darah yang menuju ke

31
ginjal berkurang. Akibatnya, ginjal akan kekurangan asupan makanan dan oksigen.
Keadaan sel ginjal kekurangan oksigen dan makanan akan menyebabkan sel ginjal
mengalami iskemia dan memacu timbulnya reaksi inflamasi yang dapat berakhir
dengan penurunan kemampuan sel ginjal dalam menyaring darah (Hidayati 2007).
Tidak adanya hubungan antara kebiasaan konsumsi minuman berenergi dan
kejadian CKD pada contoh disebabkan oleh sebaran data konsumsi minuman
berenergi yang tidak normal.
Suplemen
Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan tidak terdapat hubungan yang
signifikan antara nilai GFR (CKD) dan kebiasaan konsumsi suplemen (p=0.234,
r=0.207), serta hubungan antara nilai GFR (CKD) dan frekuensi konsumsi
suplemen (p=0.164, r=0.241). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian
Muchlisin (2011), yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang
signifikan antara kebiasaan konsumsi suplemen dan kejadian gagal ginjal kronis
p>0.05 (p=0.634). Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara nilai GFR dan
kebiasaan konsumsi suplemen pada contoh disebabkan oleh jenis suplemen yang
dikonsumsi oleh contoh. Tidak semua suplemen dapat merusak ginjal. Peneliti tidak
menghubungkan antara jenis suplemen dengan kejadian CKD, tetapi hanya
menghubungkan tingkat kebiasaannya saja. Selain itu sebaran data kebiasaan
konsumsi suplemen tidak menyebar normal, sehingga secara statistik sulit untuk
menghubungkannya (kekuatan statistik melemah).
Hubungan antara nilai GFR (CKD) dan riwayat penyakit (penyakit lain)
Hasil uji korelasi Spearman menunjukan terdapat hubungan yang signifikan
(p<0.05) antara nilai GFR (CKD) dan jenis penyakit lain (p=0.025, r=-0.378). Nilai
korelasi untuk hubungan GFR (CKD) dan jenis penyakit lain (hipertensi, diabetes
mellitus, dan komplikasi keduanya) adalah -0.378. Nilai tersebut menunjukkan
semakin tinggi nilai GFR maka komplikasi penyakit akan rendah, sebaliknya
semakin rendah nilai GFR maka komplikasi penyakit lain akan semakin tinggi.
Hasil ini sejalan dengan penelitian Ginawi IB (2012) tentang penilaian faktor risiko
yang berhubungan dengan CKD di Saudi Arabia. Pada hasil penelitiannya terdapat
hubungan yang signifikan antara CKD (serum kreatinin) dengan hipertensi
(p=0.000) dan hubungan antara CKD (seum kreatinin) dengan diabetes mellitus
(p=0.000).
Hipertensi dapat menyebabkan gagal ginjal dan gagal ginjal juga dapat
menyebabkan hipertensi. Hipertensi yang berlangsung lama dapat menyebabkan
perubahan struktur pada arteriol di seluruh tubuh, ditandai dengan fibrosis dan
hialinisasi dinding pembuluh darah. Organ sasaran utama adalah jantung, otak,
ginjal, dan mata. Pada ginjal, arteriosklerosis akibat hipertensi lama menyebabkan
nefrosklerosis. Gangguan ini merupakan akibat langsung iskemia karena
penyempitan lumen pembuluh darah intrarenal. Penyumbatan arteri dan arteriol
akan menyebabkan kerusakan glomerulus dan artrofi tubulus, sehingga seluruh
nefron rusak. Pada akhirnya terjadilah gagal ginjal kronis (Stump 2004).
Gagal ginjal kronis sendiri sering menimbulkan hipertensi. Sekitar 90%
hipertensi bergantung pada volume dan berkaitan dengan retensi cairan dan
natrium, sementara <10% bergantung pada renin. Tekanan darah adalah hasil dari
perkalian curah jantung dengan tekanan perifer. Pada gagal ginjal, volume cairan
tubuh meningkat, sehingga meningkatkan curah jantung. Keadaan ini

32
meningkatkan tekanan darah. Selain itu, kerusakan nefron akan memicu sekresi
renin yang akan mempengaruhi tahanan perifer, sehingga semakin meningkat
(Stump 2004).
Diabetes mellitus dapat menyebabkan terjadinya gagal ginjal kronis dengan
mekanisme berikut. Diabetes mellitus ditandai dengan peningkatan kadar glukosa
darah yang tidak terkontrol (hiperglikemia). Apabila kadar glukosa darah tidak
terkontrol, maka glukosa akan dikeluarkan melalui ginjal secara berlebihan.
Keadaan tersebut membuat ginjal hiperfiltrasi dan hipertrofi. Hiperfiltrasi dan
hipertrofi terus – menerus dalam kurun waktu yang lama akan menyebabkan gagal
ginjal kronis (Stump 2004).
Hubungan antara nilai GFR (CKD) dan status gizi (IMT)
Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan terdapat hubungan yang
signifikan (p<0.05) antara nilai GFR (CKD) dan status gizi (IMT) (p=0.000, r=-
0.653). Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara IMT dan nilai
GFR. Nilai korelasi -0.653 mengindikasikan bahwa semakin tinggi IMT maka nilai
GFR akan semakin turun, sebaliknya semakin normal IMT maka nilai GFR akan
semakin tinggi. Nilai GFR ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya umur, berat
badan, dan serum kreatinin (Levey 2000). Berikut adalah rumus untuk menghitung
nilai GFR.
GFR = (140−𝑢𝑚𝑢𝑟)𝑥 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛 𝑥 (0.85=𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛)
72 𝑥 𝑠𝑒𝑟𝑢𝑚 𝑘𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑖𝑛
Berdasarkan rumus untuk menghitung nilai GFR, berat badan (IMT) menjadi salah
satu faktor penentu nilai GFR. Semakin tinggi nilai berat badan (IMT), maka nilai
GFR akan semakin tinggi.
Hasil penelitian Cohen (2013) menggunakan studi cross sectional dengan
jumlah contoh 21880 orang (laki-laki:68%, perempuan:32%) menyatakan bahwa,
terdapat hubungan yang signifikan antara IMT dan nilai GFR (p<0.001). Pada
penelitiannya, IMT contoh dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu <25 Kg/m2
(normal), 25-29.9 Kg/m2 (overweight), 30-35 Kg/m2 (Obese I), dan >35 Kg/m2
(Obese II). Contoh yang memiliki IMT <25 Kg/m2 (normal) memiliki faktor
dominan yang berhubungan dengan penurunan nilai GFR sebanyak 1 kali, contoh
yang memiliki IMT 25-29.9 Kg/m2 (overweight) memiliki faktor dominan yang
berhubungan dengan penurunan nilai GFR sebanyak 3.4 kali, contoh yang memiliki
IMT 30-35 Kg/m2 (Obese I) memiliki faktor dominan yang berhubungan dengan
penurunan nilai GFR sebanyak 4.5 kali, dan contoh dengan IMT >35 Kg/m2 (Obese
II) memiliki faktor dominan yang berhubungan dengan penurunan nilai GFR 15.4
kali. Hal yang serupa juga ditemukan pada penelitian Kawamoto (2008) yang
menyatakan bahwa, semakin meningkatnya nilai IMT maka akan semakin cepat
terjadi penurunan nilai GFR.

33
Faktor dominan yang berhubungan dengan gagal ginjal kronis
Hasil dugaan persamaan faktor dominan yang berhubungan dengan gagal
ginjal kronis dan semua tanda parameter dugaan disajikan pada tabel 18 berikut.
Koefisien determinasi (R-square) menunjukkan nilai sebesar 0.600 yang berarti
penyakit gagal ginjal kronis sebesar 60% dapat dijelaskan oleh besar keluarga,
asupan makanan asin dan awetan, konsumsi air putih, status gizi, dan konsumsi
gula. Sedangkan sisanya 40% dijelaskan oleh faktor-faktor yang tidak dianalisis
dalam model. Hasil dugaan faktor dominan yang berhubungan dengan penyakit
gagal ginjal kronis disajikan pada Tabel 16.
Tabel 16 Hasil dugaan faktor dominan yang berhubungan dengan
penyakit gagal ginjal kronis
Varibel Koefisien t-hitung p
C 8.339 3.601 0.001
Besar keluarga -0.517 -2.155 0.040
Asupan makanan asin dan
awetan
-0.029 -2.280 0.030
Konsumsi air putih 0.001 2.143 0.041
Status gizi -0.401 5.521 0.000
Konsumsi gula -0.088 -3.068 0.005
R-squared 0.600
Adj R-squared 0.531
F 8.702
Significant 0.000
Uji-F menunjukkan bahwa besar keluarga, asupan makanan asin dan
awetan, konsumsi air putih, status gizi, dan konsumsi gula secara bersama-sama
dapat menjelaskan penyakit gagal ginjal kronis (CKD) dan secara statistik nyata
pada taraf 0.000. Persamaan regresi menggunakan persamaan regresi linear dan
memenuhi uji asumsi klasik berupa normalitas, homoskedastisitas, autokolerasi,
dan multikolinearitas. Berikut merupakan persamaan regresi linear yang digunakan
pada penelitian ini.
Y = 8.339 – 0.517X1 – 0.029X2 + 0.001X3 - 0.401X4 – 0.088X5
Keterangan:
Y = Nilai GFR (CKD)
X1 = Besar keluarga
X2 = Asupan makanan asin dan awetan
X3 = Konsumsi air putih
X4 = Status gizi
X5 = Konsumsi gula
Besar keluarga berhubungan negatif dan berpengaruh nyata terhadap nilai
GFR (CKD). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan persentase besar keluarga
akan menurunkan nilai GFR (CKD). Nilai parameter dugaan yang diperoleh adalah
-0.517 yang berarti jika persentase besar keluarga meningkat 1% maka nilai GFR
akan menurun 0.517% apabila variabel lain bernilai konstan. Besar keluarga

34
merupakan salah satu komponen dari sosial ekonomi. Drey et al. (2003) melakukan
penelitian tentang pengaruh sosial ekonomi terhadap peningkatan serum kretainin.
Komponen sosial ekonomi yang diukur adalah akses kesehatan, tingkat pendidikan,
dan status ekonomi. Hasilnya, orang-orang dengan akses kesehatan rendah,
pendidikan rendah, dan status ekonomi menengah ke bawah cenderung memiliki
nilai serum kreatinin yang lebih tinggi. Besar keluarga akan berpengaruh terhadap
distribusi konsumsi pangan. Peneliti menduga semakin tinggi besar keluarga, maka
distribusi konsumsi pangan akan semakin sulit. Kesulitan dalam konsumsi pangan
membuat orang untuk lebih memilih makanan jenis apa saja untuk dikonsumsi
(tanpa melihat kualitasnya). Konsumsi pangan dengan kualitas yang rendah akan
membuat kehadiran beberapa penyakit, salah satunya penyakit gagal ginjal kronis.
Asupan makanan asin dan awetan berhubungan negatif dan berpengaruh
nyata terhadap nilai GFR (CKD). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan
persentase asupan makanan asin dan awetan akan menurunkan nilai GFR (CKD).
Nilai parameter dugaan yang diperoleh adalah -0.02 yang berarti jika persentase
asupan makanan asin dan awetan meningkat 1% maka nilai GFR akan menurun
0.02% apabila variabel lain bernilai konstan. Penelitian yang dilakukan oleh Wang
et.al (2014), menyebutkan bahwa konsumsi makanan yang mengandung garam
tinggi secara signifikan berhubungan dengan kejadian hipertensi (p=0.0003).
Hanum (2014), juga menyebutkan bahwa contoh yang sering mengonsumsi
makanan asin dan awetan memiliki peluang 10 kali lipat mengalami hipertensi
dibandingkan dengan contoh yang tidak mengonsumsi makanan asin dan awetan
(OR=10.035,95% CI: 1.213-82.981). Hipertensi dalam waktu lama mengarah
kepada gagal ginjal kronis (Stump 2004).
Hipertensi telah lama dikenali sebagai penyebab, konsekuensi, dan
percepatan terhadap CKD. Pada studi cross sectional dengan partisipan remaja
Australia berusia 20 tahun menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara
hipertensi dengan kejadian CKD. Umur, jenis kelamin, dan hipertensi secara tidak
langsung berhubungan dengan penurunan GFR (Laju filtrasi glomerulus). Nilai OR
dari analisis univariat menunjukkan bahwa hipertensi sebagai faktor dominan yang
berhubungan dengan terhadap CKD sebesar 7.5 (95% CI 6.5-8.8) (Chadban et al.
2003).
Konsumsi air putih berhubungan positif dan berpengaruh nyata terhadap
nilai GFR (CKD). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan persentase konsumsi
air putih akan meningkatkan nilai GFR (CKD). Nilai parameter dugaan yang
diperoleh adalah 0.001 yang berarti jika persentase konsumsi air putih meningkat
1% maka nilai GFR akan meningkat 0.001% apabila variabel lain bernilai konstan.
Penelitian Strippoli (2011) tentang studi observasional Kohort yang melihat
hubungan antara CKD dan asupan cairan dengan menggunakan kuesioner pada
orang tua di Blue Mountain pada 2 periode waktu yang berbeda (1999-1994 dan
1997-2000) menunjukkan hasil bahwa penurunan prevalensi CKD berhubungan
dengan asupan cairan yang tinggi. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa asupan
cairan dapat menurunkan kejadian CKD kira-kira 50%.
Status gizi berhubungan negatif dan berpengaruh nyata terhadap nilai GFR
(CKD). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan persentase status gizi akan
meningkatkan nilai GFR (CKD). Nilai parameter dugaan yang diperoleh adalah
0.401 yang berarti jika persentase status gizi meningkat 1% maka nilai GFR akan
menurun 0.401% apabila variabel lain bernilai konstan. Parameter status gizi yang

35
digunakan pada penelitian ini adalah IMT. Status gizi yang berlebih (tinggi)
berhubungan dengan obesitas. Banyak penelitian yang telah melihat hubungan
antara obesitas dan nilai GFR. Pada studi Kohort yang melibatkan 101516 pria dan
wanita jepang menunjukkan bahwa IMT berhubungan terbalik dengan kejadian
penyakit gagal ginjal kronis pada wanita tetapi tidak pada pria (Iseki 1997).
Sebaliknya pada penelitian lain menggunakan studi cross sectional menunjukkan
bahwa terdapat hubungan yang positif antara persentase lemak tubuh dan IMT
dengan nilai GFR pada pasien CKD (Kopple 2000). Obesitas merupakan salah satu
penyebab tidak langsung hipertensi dan diabetes mellitus. Hipertensi dan diabetes
mellitus merupakan penyebab tersering kejadian gagal ginjal kronis (Stump 2004).
Konsumsi gula berhubungan negatif dan berpengaruh nyata terhadap nilai
GFR (CKD). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan persentase konsumsi gula
akan menurunkan nilai GFR (CKD). Nilai parameter dugaan yang diperoleh 0.088
yang berarti jika persentase konsumsi gula meningkat 1% maka nilai GFR akan
menurun 0.088% apabila variabel lain bernilai konstan. Konsumsi gula yang
berlebih ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah
yang terlalu tinggi akan membuat kerja insulin ekstra. Ada saatnya insulin tidak
mampu lagi untuk mengontrol kadar glukosa darah yang terlalu tinggi, sehinnga hal
ini menjadi suatu penyakit, yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus berkaitan
dengan kejadian gagl ginjal kronis. Orang yang menderita diabetes mellitus akan
kesulitan dalam menurunkan kadar glukosa darahnya, karena insulin telah rusak.
Oleh karena itu kadar glukosa darah yang tinggi akan dibuang melalui ginjal,
sehingga membuat ginjal hiperfiltrasi. Hiperfiltrasi dalam jangka waktu yang lama
akan menyebabkan ginjal rusak (Stump 2004).
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Lebih dari setengah contoh (54.3%) berjenis kelamin laki – laki. Sebagian
besar contoh (71.4%) tergolong ke dalam usia ≥45 tahun. Sebesar 94.3% contoh
beragama islam. Sebesar 37.1% contoh memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah
tangga. Tingkat pendidikan contoh sebagian besar adalah tamat SMA (57.1%).
Sebagian besar contoh (88.6%) memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan.
Sebagian besar contoh (60%) tergolong ke dalam kategori keluarga kecil (≤4
orang). Lebih dari setengah dari jumlah contoh (51.4%) memiliki kebiasaan
merokok. Hanya 9 (25.7%) yang memiliki riwayat konsumsi alkohol. Sebagian
besar contoh (68.6%) terbiasa melakukan olahraga. Golongan makanan pokok yang
paling sering dikonsumsi contoh adalah nasi, kentang, roti putih, bihun, dan
singkong. Golongan lauk pauk yang paling sering dikonsumsi contoh adalah tahu,
telur, daging sapi, tempe, dan ikan segar. Golongan sayuran yang sering dikonsumsi
contoh adalah sayur sup, daun singkong, sayur asem, wortel, dan sawi. Golongan
buah yang paling sering dikonsumsi contoh adalah pisang, pepaya, semangka,

36
jeruk, dan apel. Golongan susu dan hasil lahannya yang paling sering dikonsumsi
contoh adalah susu bubuk dan susu segar.
Golongan makanan asin dan awetan yang paling sering dikonsumsi contoh
adalah sarden, naget, keju, sosis, dan kerupuk asin. Golongan makanan berlemak
yang paling sering dikonsumsi contoh adalah telur ayam, daging ayam dengan kulit,
gorengan, daging sapi, dan udang. Golongan bumbu yang paling sering dikonsumsi
contoh adalah kecap manis, garam, saus tomat/sambal, dan kecap asin. Sebagian
besar contoh (71.4%) minum air putih <8 gelas/hari. Sebesar 51.4% contoh
memiliki kebiasaan konsumsi minuman berenergi. Lebih dari setengah dari jumlah
contoh (51.4%) tidak mengonsumsi suplemen. Sebesar 30% dari jumlah contoh
memiliki penyakit lain selain CKD, meliputi 53.3% hipertensi, 20% diabetes
mellitus, dan 26.7% komplikasi keduanya. Kurang dari setengah dari jumlah contoh
(28.6%) memiliki status gizi normal.
Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan terdapat hubungan yang
signifikan antara usia dan konsumsi suplemen (p=0.000,r=-0.346), usia dan
frekuensi konsumsi suplemen (p=0.042,r=-0.402), pendidikan dan konsumsi
suplemen (p=0.018,r=0.398), GFR dan penyakit lain (p=0.025,r=-0.378), serta
hubungan antara GFR dan IMT (status gizi) (p=0.000,r=-0.653).
Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan tidak terdapat hubungan yang
signifikan (p>0.05) antara GFR dan kebiasaan merokok, GFR dan kebiasaan
konsumsi alkohol, GFR dan kebiasaan olahraga, GFR dan kebiasaan konsumsi
makanan asin dan awetan, GFR dan kebiasaan konsumsi makanan berlemak,
kebiasaan konsumsi bumbu dan gula, kebiasaan konsumsi air, kebiasaan konsumsi
suplemen, kebiasaan konsumsi dan minuman berenergi. Berdasarkan analisis
multivariat menggunakan regresi linear variabel yang berhubungan dengan CKD
adalah besar keluarga (p=0.040), asupan makanan asin dan awetan (p=0.030),
konsumsi air putih (p=0.041), status gizi (p=0.000), dan konsumsi gula (p=0.005).
Saran
Prevalensi penyakit gagal ginjal kronis di Indonesia semakin meningkat
setiap tahun, terutama di Jakarta mengingat pola gaya hidup masyarakat yang telah
berubah. Jumlah keluarga yang terlalu besar, konsumsi makanan asin dan awetan,
dan konsumsi gula yang berlebihan seharusnya dikurangi, sebaliknya konsumsi air
putih lebih ditingkatkan. Berat badan diharapkan ideal untuk mencapai status gizi
optimal untuk mencegah penyakit gagal ginjal kronis. Desain penelitian ini adalah
cross sectional. Desain tersebut kurang menggambarkan hubungan sebab akibat.
Sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan dengan desain yang lebih baik dalam
menggambarkan hubungan sebab akibat, sehingga dapat menjelaskan faktor
dominan yang berhubungan dengan gagal ginjal kronis lebih baik. Desain yang
disarankan seperti desain case control pada contoh dewasa dengan penyakit gagal
ginjal kronis.

37
DAFTAR PUSTAKA
Aufa S, Masbar R, Nasir M. 2013. Pengaruh pendapatan per kapita, pertumbuhan
penduduk, dan tingkat upah terhadap biaya hidup di Indonesia. Jurnal Ilmu
Ekonomi.1(1):64-76.
Bailey RL, Gahche JJ, Lentino CV, Dwyer JT, Engel JS, Thomas PR, Betz JM,
Sempos CT, Picciano MF. 2003-2006. 2011. Dietary supplement use in
the United States, 2003-2006. J Nutr. 14(2):261-266.
Balluz et al. 2000. Vitamin and mineral supplement use in the United States:results
from the third national health and nutrition examination survey. American
Medical Association 2000.9:258-262.
Battistella M. 2012. Management of depression in hemodialysis patient. The
CANNT Journal. 22 (3): 29-34.
BKKBN. 1998. Paket Pelatihan Pendidikan Keluarga Berencana. BKKBN.
Jakarta (ID).
Bleyer AJ, Shemanski LR, Burke GL. 2000. Tobacco, hypertension, and vascular
disease: risk factors for renal functional decline in an older population.
Kidney International. 57: 2072-9.
BPOM. 2004. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor HK.00.05.23.3644 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan
Suplemen Makanan. Jakarta (ID):BPOM.
Chadban SJ, Briganti EM, Kerr PG. 2003. Prevalence of kidney damage in
Australian adults; the ausdiab kidney study. Journal of the American
Society of Nephrology. 14:8-131.
Dinkinson, Mackay. 2014. Health habits and other characteristics of dietary
supplement users.Nutrition Journal.13(1):2-8.
Drey N, Roderick P, Mullee M. 2003. A population-based study of the incidence
and outcomes of diagnosed chronic kidney disease. American Journal of
Kidney Diseases. 42: 677-84.
Eidemak I, Haaber AB, Feldt-Rasmussen B. 1997. Exercise training and the
progression of chronic renal failure. Nephron.75:36-40.
Eytan C, Abigail F, Elad G, Gai M, Moshe G, Ilan K. 2013. Assosiation between
the body mass index and chronic kidney disease in men and women- a
population based- study from Israel. Nephrol Dial Transplant. 28(4):30-
35.
Fox CS, Larson MG, Leip EP. 2004. Predictors of new-onset kidney disease in a
community based population. JAMA. 291:50-844.
Ginawi IB, Ahmed HG, Alhazimi AM. 2012. Assesment of risk factors for chronic
kidney disease in Saudi Arabia. Internation Journal of Science and
Research (IJSR). 3(7):446-450.

38
Grassi G, Seravalle G, Calhoun DA, Bolla GB, Giannattasio CG, Marabini M, Del
BO, Mansia G. 1994. Mechanisms responsible for sympathetic activation
by cigarret smoking in humans; Circulation. 90: 248-253.
Greger JI. 2001. Dietary supplement use:consumer characteristics and interest.
Journal of Nutrition.131:13395-13435.
Hanum NH. 2014. Faktor risiko hipertensi pada pekerja garmen wanita [skripsi].
Bogor (ID): IPB
Haroun MK, Jaar BG, Hoffman SC. 2003. Risk factors of chronic kidney disease :
a prospective study of 23.534 men and women in Washington country,
Maryland. Journal of the American Society of Nephrology. 14:41-2934.
Hidayati, Titiek. 2008. Hubungan Antara Hipertensi, Merokok dan Minuman
Supelemen Energi dan Kejadian Penyakit Ginjal Kronis. Tesis, Program
Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. 90-102.
Iseki K, Ikemiya Y, Fukiyama K. 1997. Risk factors of end stage renal disease and
serum creatinine in a community based mass screening. Kidney
International.51:850-4.
Ishihara J et al. 2003. Demographics, lifestyle, health characteristics and dietary
intake among dietary supplement users in Japan. International Journal of
Epidemiology.32:533-546.
John R, Webb M, Young A. 2004. Unreferred chronic kidney disease : a
longitudinal study. American Journal of Kidney Diseases. 43:35-825.
Jones-Burton C, Seliger SL, Scherer RW. 2007. Cigarette smoking and incident
chronic kidney disease: a systematic review. American Journal of
Nephrology. 27: 342-51.
Kawamoto R, Kohara K, Tabara Y, Miki T, Ohtsuka N, Kusunoki T, Yorimitsu N.
2008. An assosiation between body mass index and estimated glomerular
filtration rate. Hipertense Res.31(8):1559-1564.
[Kemenkes RI] Kementeran Kesehatan RI. 2013. Laporan Nasional Hasil Riset
Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013. Jakarta (ID): Balitbangkes RI.
Khairunnisa A. 2012. Faktor – faktor yang berhubungan dengan nafsu makan
kurang pada pasien hemodialisis di RSPAD Gatot Soebroto [skripsi].
Jakarta (ID): Universitas Indonesia.
Koople JD, Greene T, Chumlea WC. 2000. Relationship between nutritional status
and the glomerular filtration rate:results from the MDRD study. Kidney
International.57:1688-703.
Koplan et al. 1996. Nutrition intake and supplementation in United States
(NHANESS III). American Journal Public Health.76:287-289.
Levey AS, Greene T, Kusek JW, Beck GJ: A simplified equation to predict
glomerular filtration rate from serum creatinine [Abstract]. J Am Soc
Nephrol 11: 155A, 2000 (Rumus GFR).
Maria C, Johnson D. 1997. Modification of lifestyle and nutrition interventions for
management of chronic kidney disease. Kidney Health Australia.1-50

39
Messerer et al. 2001. Sociodemographig and health behaviour factor among dietary
supplement and natural remedy users. European Journal of Clinical
Nutrition.55(12):104-110.
Orth SR, Ogata H, Ritz E. 2000. Smoking and kidney. Nephrol Dial Transplant.
15:1509-1511.
Parekh RS, Klag MJ. 2001. Alcohol: role in the development of hypertension and
end-stage renal disease. Current Opinion in Nephrology &
Hypertension.10: 385-90.
Perneger TV, Whelton PK, Puddey IB. 1999. Risk of end-stage renal disease
associated with alcohol consumption. Am J Epidemiol.150:1275–81.
Radimer K, Bindewald B, Hughes J, Ervin B, Swanson C, Picciano MF, 1999-2000.
2004. Dietary supplement use by US adults: data from the National Health
and Nutrition Examination Survey. Am J Epidemiol. 160(4):339-349.
Restu P, Woro S. 2015. Risk factors chronic renal failure on hemodialysis unit in
RSUD Wates Kulon Progo. Majalah Farmaseutik.11(2):316-320.
Samet JM, Wiggins C, Humble GC, Pathak RD. 1998. Cigarette smoking and lung
cancer in New Mexico. American journal of Respiratory and Critical Care
Medicine. doi: 10.1164/ajrccm/137.5.1110.
Sarjono, Ajeng H. 2010. Faktor-faktor yang berhubungan dengan konsumsi
suplemen makanan pada mahasiswa rumpun kesehatan dan non kesehatan
di Universitas Indonesia tahun 2010 [skripsi]. Jakarta (ID):Universitas
Indonesia.
Sayogyo. 2002. Kemiskinan danIndikator Kemiskinan. Jakarta (ID):Gramedia.
Shankar A, Klein R, Klein BEK. 2006. The association among smoking, heavy
drinking, and chronic kidney disease. American Journal of
Epidemiology.164: 263-71.
Strippoli GFM, Craig JC, Rochtchina E. 2011. Fluid and nutrient intake and risk of
chronic kidney disease. Nephrology.16: 326-334.
Stump SE. 2004. Krause’s Food, Nutrition, and Diet Therapy 11th Edition.
USA:Elsevier
Suhardjo. 1989. Sosio Budaya Gizi. Bogor (ID):IPB
[USRDS] United States Renal Data System. 2009.
http://www.usrds.org/2009/pdf/V1_00_INTROL_09.PDF [Internet].
[Diunduh 9 Maret 2016.
Wang et al. 2014. Fruit and vegetable intake and the risk of hypertension in middle
age and older women. American Journal Hypertension. 25(2):180-9

40

41
RIWAYAT HIDUP
Penulis lahir di Indrapura, Kabupaten Batu Bara, Medan, Provinsi Sumatera
Utara pada tanggal 13 Desember 1994 dari pasangan Abu Bakar dan Syamsiah
Damanik. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis memulai
pendidikan dari SDN 010213 Tanah Merah tahun 2001-2007. Setelah itu penulis
melanjutkan pendidikan ke SMPN 3 Air Putih tahun 2007-2010 dan SMAN 1 Air
Putih tahun 2009-2012. Tahun 2012 penulis melanjutkan studi di Institut Pertanian
Bogor (IPB) jurusan Gizi Masyarakat melalui jalur SNMPTN Undangan.
Selama masa studi, penulis merupakan pengurus BEM FEMA (Badan
Eksekutif Mahasiswa) pada tahun 2014 menjadi anggota pada divisi PBOS
(Pengembangan Olahraga dan Seni). Penulis juga aktif mengikuti kegiatan
kepanitiaan, seperti Nutrition Fair 2013 dan 2014 sebagai anggota Divisi Acara dan
penanggung jawab Phytosterol, Gizi Bakti Masyarakat sebagai anggota pada tahun
2013 dan 2014 sebagai anggota, dan ESPENT (Ecology Sport and Art Event) tahun
2015 sebagai ketua Divisi Acara. Tahun 2015 penulis melakukan Kuliah Kerja
Nyata-Praktik (KKN-P) di desa Klaces, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten
Cilacap. Pada kegiatan KKN-P, penulis mendapatkan pengalaman untuk
memberikan makanan tambahan, edukasi gizi dan monitoring terhadap balita gizi
kurang di daerah tersebut. Penulis juga mengikuti serangkaian kegiatan Posyandu
di desa tersebut. Pada bulan Desember 2015-Januari 2016, penulis melakukan
Internship Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan dan Dietetik di Rumah
Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Ditkesad, Jakarta.

42