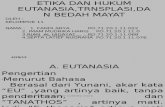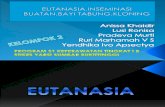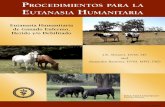eutanasia
-
Upload
indra-sajha -
Category
Documents
-
view
10 -
download
1
description
Transcript of eutanasia
BAB I
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sejauh ini Indonesia memang belum mengatur secara spesifik mengenai euthanasia (Mercy Killing). Euthanasia atau menghilangkan nyawa orang atas permintaan dirinya sendiri, sama dengan perbuatan pidana menghilangkan nyawa seseorang. Dan hal ini masih menjadi perdebatan pada beberapa kalangan yang menyetujui tentang euthanasia dan pihak yang tidak setuju tentang euthanasia.
Pihak yang menyetujui euthanasia dapat dilakukan, hal ini berdasarkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan hak untuk mengakhiri hidupnya dengan segera dan hal ini dilakukan dengan alasan yang cukup mendukung yaitu alasan kemanusian. Dengan keadaan dirinya yang tidak lagi memungkinkan untuk sembuh atau bahkan hidup, maka ia dapat melakukan permohonan untuk segera diakhiri hidupnya.
Sementara sebagian pihak yang tidak membolehkan euthanasia beralasan bahwa setiap manusia tidak memiliki hak untuk mengakhiri hidupnya, karena masalah hidup dan mati adalah kekuasaan mutlak Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia.
Perdebatan ini tidak akan pernah berakhir, karena sudut pandang yang dipakai sangatlah bertolak belakang, dan lagi-lagi alasan perdebatan tersebut adalah masalah legalitas dari perbuatan euthanasia. Walaupun pada dasarnya tindakan euthanasia termasuk dalam perbuatan tindak pidana yang diatur dalam pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).Di Negara-negara Eropa (Belanda) dan Amerika tindakan euthanasia mendapatkan tempat tersendiri yang diakui legalitasnya, hal ini juga dilakukan oleh Negara Jepang.
Tentunya dalam melakukan tindakan euthanasia harus melalui prosedur dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar euthanasia bias dilakukan.Ada tiga petunjuk yang dapat digunakan untuk menentukan syarat prasarana luar biasa. Pertama, dari segi medis ada kepastian bahwa penyakit sudah tidak dapat disembuhkan lagi.
Kedua, harga obat dan biaya tindakan medis sudah terlalu mahal. Ketiga, dibutuhkan usaha ekstra untuk mendapatkan obat atau tindakan medis tersebut. Dalam kasus-kasus seperti inilah orang sudah tidak diwajibkan lagi untuk mengusahakan obat atau tindakan medis. Bahkan, euthanasia dengan menyuntik mati disamakan dengan tindakan pidana pembunuhan. Alternatif terakhir yang mungkin bisa diambil adalah penggunaan sarana via extraordinaria. Jika memang dokter sudah angkat tangan dan memastikan secara medis penyakit tidak dapat disembuhkan serta masih butuh biaya yang sangat besar jika masih harus dirawat, apalagi perawatan harus diusahakan secara ekstra, maka yang dapat dilakukan adalah memberhentikan proses pengobatan dan tindakan medis dirumah sakit.
Di Indonesia masalah euthanasia masih belum mandapatkan tempat yang diakui secara yuridis dan mungkinkah dalam perkembangan Hukum Positif Indonesia, euthanasia akan mendapatkan tempat yang diakui secara yuridis. Kasus yang terakhir yang pengajuan permohonan euthanasia oleh suami Again ke Pengadilan Negeri Jakarta, belum dikabulkan.Dan akhirnya korban yang mengalami koma dan ganguan permanent pada otaknya sempat dimintakan untuk dilakukan euthanasia, dan sebelum permohonan dikabulkan korban sembuh dari komanya dan dinyatakansehatolehdokter. Apabila hukum di Indonesia kelak mau menjadikan persoalan euthanasia sebagai salah satu materi pembahasan, semoga tetap diperhatikan dan dipertimbangkan sisi nilai-nilainya, baik sosial, dan moral.
B. Rumusan Masalah
Menyangkut feomena yang ada akan menimbulkan beberapa permasalahan yang harus kita selesaikan dengan seksama. Dari latar belakang demikian ini penulis mendapatkan beberapa permasalahan yang akan kita bahas dalam bab-bab berikutnya antara lain;
1. Apakah dimungkinkan adanya terobosan baru alam hukum berdasarkan kasus-kasus berat, seperti secara medis penyakit sudah tidak bisa lagi disembuhkan, sementara dokter pun sudah angkat tangan?
2. Mengingat hukum kita menganut positifistik, bagaimana Euthanasia menurut persepektif hukum Pidana Indonesia?
C. Metode Penulisan
Penulisan makalah ini dilakukan dengan metode studi pustaka.
D. Tujuan
Adapun tujuan dari penuliasan makalah yang berjudul Pro dan Kontra Euthanasia adalah :
1. Untuk memberikan pengetahuan mengenai euthanasia itu sendiri dan menambah pengetahuan mengenai perawat dan dokter dalam menghadapi masalah euthanasia.2. Melatih penulis untuk mengembangkan bakat dan ilmunya dalam penulisan makalah.
BAB IITINJAUAN PUSTAKA
A. Definisi Euthanasia
Mati sesungguhnya masalah yang sudah pasti terjadi, akan tetapi tidak pernah diketahui dengan tepat kapan saatnya terjadi. Pengertian tentang kematian itu sendiri mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kematian dapat dibagi menjadi 2 fase, yaitu: somatic death (Kematian Somatik) dan biological death (Kematian Biologik). Kematian somatik merupakan fase kematian dimana tidak didapati tanda tanda kehidupan seperti denyut jantung, gerakan pernafasan, suhu badan yang menurun dan tidak adanya aktifititas listrik otak pada rekaman EEG. Dalam waktu 2 jam, kematian somatik akan diikuti fase kematian biologik yang ditandai dengan kematian sel. Kurun waktu 2 jam diantaranya dikenal sebagai fase mati suri. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan seperti alat respirator (alat bantu nafas), seseorang yang dikatakan mati batang otak yang ditandai dengan rekaman EEG yang datar, masih bisa menunjukkan aktifitas denyut jantung, suhu badan yang hangat, fungsi alat tubuh yang lain seperti ginjalpun masih berjalan sebagaimana mestinya, selama dalam bantuan alat respirator tersebut. Tanda tanda kematian somatik selain rekaman EEG tidak terlihat. Tetapi begitu alat respirator tersebut dihentikan, maka dalam beberapa menit akan diikuti tanda kematian somatik lainnya. Walaupun tanda tanda kematian somatik sudah ada, sebelum terjadi kematian biologik, masih dapat dilakukan berbagai macam tindakan seperti pemindahan organ tubuh untuk transplantasi, kultur sel ataupun jaringan dan organ atau jaringan tersebut masih akan hidup terus, walaupun berada pada tempat yang berbeda selama mendapat perawatan yang memadai. Jadi dengan demikian makin sulit seorang ilmuwan medik menentukan terjadinya kematian pada manusia. Apakah kematian somatik secara lengkap harus terlihat sebagai tanda penentu adanya kematian, atau cukup bila didapati salah satu dari tanda kematian somatik, seperti kematian batang otak saja, henti nafas saja atau henti detak jantung saja sudah dapat dipakai sebagai patokan penentuan kematian manusia. Permasalahan penentuan saat kematian ini sangat penting bagi pengambilan keputusan baik oleh dokter maupun keluarganya dalam kelanjutan pengobatan. Apakah pengobatan dilanjutkan atau dihentikan. Dilanjutkan belum tentu membawa hasil, tetapi yang jelas akan menghabiskan materi, sedangkan bila dihentikan pasti akan membawa kefase kematian. Penghentian tindakan pengobatan ini merupakan salah satu bentuk dari euthanasia. Berdasarkan pada cara terjadinya, ilmu pengetahuan membedakan kematian ke dalam tiga jenis, yaitu:
1.Orthothanasia, yaitu kematian yang terjadi karena proses alamiah.
2. Dysthanasia, yaitu kematian yang terjadi secara tidak wajar.
3.Euthanasia, yaitu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter.
Euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu yang berarti indah, bagus, terhormat atau gracefully and with dignity, dan thanatos yang berarti mati. Jadi secara etimologis, euthanasia dapat diartikan sebagai mati dengan baik. Jadi sebenarnya secara harafiah, euthanasia tidak bisa diartikan sebagai suatu pembunuhan atau upaya menghilangkan nyawa seseorang. Menurut Philo (50-20 SM) euthanasia berarti mati dengan tenang dan baik, sedangkan Suetonis penulis Romawi dalam bukunya yang berjudul Vita Ceasarum mengatakan bahwa euthanasia berarti mati cepat tanpa derita Euthanasia dalam Oxford English Dictionary dirumuskan sebagai kematian yang lembut dan nyaman, dilakukan terutama dalam kasus penyakit yang penuh penderitaan dan tak tersembuhkan. Istilah yang sangat populer untuk menyebut jenis pembunuhan ini adalah mercy killing (Tongat, 2003 :44). Sementara itu menurut Kamus Kedokteran Dorland euthanasia mengandung dua pengertian. Pertama, suatu kematian yang mudah atau tanpa rasa sakit. Kedua, pembunuhan dengan kemurahan hati, pengakhiran kehidupan seseorang yang menderita penyakit yang tak dapat disembuhkan dan sangat menyakitkan secara hati-hati dan disengaja. Sejak abad 19 terminologi euthanasia dipakai untuk penghindaran rasa sakit dan peringanan pada umumnya bagi yang sedang menghadapi kematian dengan pertolongan. dokter.
B. Jenis Euthanasia
Secara konseptual dikenal tiga bentuk euthanasia, yaitu :
1. voluntary euthanasia yaitu euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien itu sendiri karena penyakitnya tidak dapat disembuhkan dan dia tidak sanggup menahan rasa sakit yang diakibatkannya
2. non voluntary euthanasia yaitu di sini orang lain, bukan pasien, mengandaikan, bahwa euthanasia adalah pilihan yang akan diambil oleh pasien yang berada dalam keadaan tidak sadar tersebut jika si pasien dapat menyatakan permintaannya
3. involuntary euthanasia yaitu merupakan pengakhiran kehidupan pada pasien tanpa persetujuannya
.
Selain diatas euthanasia juga di bedakan menjadi 2 kompartmen yang mudah dipahami yaitu :
1. Euthanasia pasif yaitu di mana tenaga medis tidak lagi memberikan atau melanjutkan bantuan medis.
2. Euthanasia aktif yaitu baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana dokter dengan sengaja melakukan tindakan untuk mengakhiri hidup pasien.
BAB IIIPEMBAHASANB. Pro Euthanasia
Euthanasia merupakan langkah terakhir yang terpaksa harus ditempuh oleh pihak medis maupun keluarga guna membantu pasien untuk menghilangkan penderitaan. Tindakan ini mungkin akan mendapatkan banyak hujatan dari pihak yang kontra euthanasia, tapi dilihat dari berbagai aspek maka euthanasia sah-sah saja untuk dilaksanakan.
Aspek Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia selalu dikaitkan dengan hak hidup, damai dan sebagainya. Tapi tidak tercantum dengan jelas adanya hak seseorang untuk mati. Mati sepertinya justru dihubungkan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini terbukti dari aspek hukum euthanasia, yang cenderung menyalahkan tenaga medis dalam euthanasia. Sebetulnya dengan dianutnya hak untuk hidup layak dan sebagainya, secara tidak langsung seharusnya terbersit adanya hak untuk mati, apabila dipakai untuk menghindarkan diri dari segala ketidak nyamanan atau lebih tegas lagi dari segala penderitaan yang hebat.
Aspek Ilmu Pengetahuan
Pengetahuan kedokteran dapat memperkirakan kemungkinan keberhasilan upaya tindakan medis untuk mencapai kesembuhan atau pengurangan penderitaan pasien. Apabila secara ilmu kedokteran hampir tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan kesembuhan ataupun pengurangan penderitaan, apakah seseorang tidak boleh mengajukan haknya untuk tidak diperpanjang lagi hidupnya? Segala upaya yang dilakukan akan sia sia, bahkan sebaliknya dapat dituduhkan suatu kebohongan, karena di samping tidak membawa kepada kesembuhan, keluarga yang lain akan terseret dalam pengurasan dana. Maka Euthanasia merupakan jalan keluar yang dapat membantu pasien dan keluarga.
Aspek Agama
Kelahiran dan kematian merupakan hak dari Tuhan sehingga tidak ada seorangpun di dunia ini yang mempunyai hak untuk memperpanjang atau memperpendek umurnya sendiri. Pernyataan ini menurut ahli ahli agama secara tegas melarang tindakan euthanasia, apapun alasannya. Dokter bisa dikategorikan melakukan dosa besar dan melawan kehendak Tuhan yaitu memperpendek umur. Orang yang menghendaki euthanasia, walaupun dengan penuh penderitaan bahkan kadang kadang dalam keadaan sekarat dapat dikategorikan putus asa, dan putus asa tidak berkenan dihadapan Tuhan. Tapi putusan hakim dalam pidana mati pada seseorang yang segar bugar, dan tentunya sangat tidak ingin mati, dan tidak dalam penderitaan apalagi sekarat, tidak pernah dikaitkan dengan pernyataan agama yang satu ini. Aspek lain dari pernyataan memperpanjang umur, sebenarnya bila dikaitkan dengan usaha medis bisa menimbulkan masalah lain. Mengapa orang harus kedokter dan berobat untuk mengatasi penyakitnya, kalau memang umur mutlak di tangan Tuhan, kalau belum waktunya, tidak akan mati. Kalau seseorang berupaya mengobati penyakitnya maka dapat pula diartikan sebagai upaya memperpanjang umur atau menunda proses kematian. Jadi upaya medispun dapat dipermasalahkan sebagai melawan kehendak Tuhan. Dalam hal hal seperti ini manusia sering menggunakan standar ganda. Hal hal yang menurutnya baik, tidak perlu melihat pada hukum hukum yang ada, atau bahkan mencarikan dalil lain yang bisa mendukung pendapatnya, tapi pada saat manusia merasa bahwa hal tersebut kurang cocok dengan hatinya, maka dikeluarkanlah berbagai dalil untuk menopangnya.
C. Kontra Euthanasia
Mengapa manusia harus berilmu karena manusia pada dasarnya ingin mewujudkan makna hidupnya baik yang menyangkut material, imaterial maupun suasana batinnya, karena segala macam upaya dilakukan untuk mendapatkan ilmu.
Ilmu yang oleh banyak orang dikatakan bebas nilai, seringkali harus berhadapan dengan kenyataan hidup dalam konteks relasi sosial. Karenanya kemudian timbul istilah etika ilmu pengetahuan, walaupun etika itu sendiri tidak termasuk dalam kawasan ilmu. Hal-hal seperti ini akan sangat jelas terasa pada ilmu-ilmu yang secara langsung dan segera berhubungan dengan kebutuhan manusia, seperti ilmu biologi, kedokteran dan lainnya yang dekat dengan kebutuhan primer manusia.
Menghadapi realita semacam itu maka sangat terasa untuk memasukkan dimensi etis dalam pengembangan ilmu maupun penerapan ilmu dalam kehidupan keseharian. Sebagai contoh teknologi transgenik, cloning merupakan isu yang banyak menyita perhatian umat manusia karena menyangkut secara langsung kehidupannya. Ketika ditemukan teknologi operasi plastik untuk merubah bentuk bagian-bagian tubuh serta teknologi sejenisnya, perdebatan diantara pihak yang pro maupun kontra nampak nyata terletak pada perdebatan dimensi etika dan bukan pada ilmu/teknologinya itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi etika tidak dapat dipisahkan dengan ilmu itu sendiri. Walaupun dilain pihak ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dan tidak perlu dicegah perkembangannya. Apalagi ilmu yang menyangkut langsung kepada keputusan tentang hidup matinya manusia yaitu Euthanasia dapat dipastikan menjadi bahan perdebatan yang tidak saja menyangkut dimensi etis, tetapi telah melibatkan dimensi-dimensi lain yang masing-masing memiliki standar/ukuran kebenaran.
Bila kembali pada kebenaran yang menjadi pijakan dalam pengembangan ilmu, serta realitas adanya berbagai macam ilmu, maka setiap ilmu harus dinilai dengan standarnya sendiri. Selanjutnya dalam rangka situasi sosial yang ada maka penilaian tersebut akan dengan sendirinya bersifat relatif.
Dalam euthanasia, setidaknya terdapat empat macam ilmu yang terlibat didalamnya yaitu hukum, hak asasi, biologi/kedokteran dan agama, yang pasti masing-masing memiliki standar kebenaran yang berbeda. Pertanyaannya tentu bagaimana proses keputusan euthanasia harus diambil untuk dapat dilaksanakan tanpa melanggar kebenaran masing-masing, untuk itu tidak ada jalan lain, selain mengikuti kebenaran relatif.
Etika, sering lebih terasa digunakan sebagai pijakan oleh praktisi ilmu, dibanding pihak yang mengembangkan ilmu itu sendiri. Profesi-profesi seperti ahli hukum, dokter dan sebagainya merupakan praktisi ilmu yang sering dituntut secara kuat etikanya dalam menerapkan ilmunya. Pertanyaannya adalah etika yang mana yang harus digunakan oleh seorang praktisi ilmu. Lebih lanjut apabila beberapa ilmu harus berperan secara bersama-sama, maka etika yang harus digunakan tentu diutamakan etika yang berlaku bagi masyarakat pengguna ilmu tersebut.
Ilmu yang seharusnya menjadikan hidup lebih mudah, lebih nikmat, lebih efisien dan sebagainya, seringkali justru membelenggu hakekat sebagai manusia, bahkan dapat secara nyata menghancurkan kehidupan. Kekecewaan Einstein terhadap penggunaan hukum fisika modern dalam kasus Hiroshima ; kemajuan teknologi industri di satu pihak dan polusi yang ditimbulkannya merupakan contoh bahwa kemajuan ilmu memiliki dua sisi yang saling kontradiktif. Demikian pula penemuan-penemuan dibidang kedokteran seringkali sangat mudah dilihat sisi positif dan negatifnya, seperti penggunaan bahan dalam anestesi, teknik-teknik pembedahan, fertilitas, euthanasia dan sebagainya. Kenyataan tersebut menunjukkan semakin jelas bahwa ilmu bersifat bebas nilai. Disinilah pentingnya norma dan etika dalam penggunaan ilmu, yang hendaknya menjadi konsensus bagi umat manusia. Klaim-klaim hukum terhadap tindakan dokter dalam euthanasia merupakan bentuk lain dari sisi negatif dalam penerapan ilmu, yang terkadang sama sekali tidak terbayangkan oleh dokter yang bersangkutan.
Jadi perkembangan ilmu yang kemudian diujudkan dalam tindakan berkembang dalam kebudayaan manusia serta sekaligus mempengaruhi kebudayaan manusia melalui dua sisi tersebut, pada gilirannya tentu dapat berupa manfaat dan atau bencana. Demikian pula euthanasia dapat hadir diantara manfaat dan bencana.
Dalam hal ini sebagi seorang individu penulis memiliki hak untuk berpendapat mengenai euthanasia. Euthanasia merupakan suatu tindakan controversial, hal ini ditentukan dari sudut pandang yang mana kita melihatnya. Penulis sercara tegas menentang keras tindakan Euthanasia dengan alasan dan berbagai perspektif.Munculnya pro dan kontra seputar persoalan euthanasia menjadi beban tersendiri bagi komunitas hukum. Sebab, pada persoalan legalitas inilah persoalan euthanasia akan bermuara. Kejelasan tentang sejauh mana hukum (pidana) positif memberikan regulasi/pengaturan terhadap persoalan euthanasia akan sangat membantu masyarakat di dalam menyikapi persoalan tersebut. Lebih-lebih di tengah kebingungan kultural karena munculnya pro dan kontra tentang legalitasnya. Patut menjadi catatan, bahwa secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal satu bentuk euthanasia, yaitu euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien/korban itu sendiri (voluntary euthanasia) sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Pasal 344 KUHP. Pasa l344 KUHP secara tegas menyatakan : :
Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun.
Bertolak dari ketentuan Pasal 344 KUHP tersebut tersimpul, bahwa pembunuhan atas permintaan korban sekalipun tetap diancam pidana bagi pelakunya. Dengan demikian, dalam konteks hukum positif di Indonesia euthanasia tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Dengan demikian dalam konteks hukum positif di Indonesia, tidak dimungkinkan dilakukan pengakhiran hidup seseorang sekalipun atas permintaan orang itu sendiri. Perbuatan tersebut tetap dikualifikasi sebagai tindak pidana, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka munculnya kasus permintaan tindakan medis untuk mengakhiri kehidupan yang muncul akhir-akhir ini. (kasus Hasan Kesuma yang mengajukan suntik mati untuk istrinya, Ny. Agian dan terakhir kasus Rudi Hartono yang mengajukan hal yang sama untuk istrinya, Siti Zuleha) perlu dicermati secara hukum. Kedua kasus ini secara konseptual dikualifikasi sebagai non voluntary euthanasia, tetapi secara yuridis formal (dalam KUHP) dua kasus ini tidak bisa dikualifikasi sebagai euthanasia sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP. Secara yuridis formal kualifikasi (yang paling mungkin) untuk kedua kasus ini adalah pembunuhan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, atau pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP secara tegas dinyatakan, Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sementara dalam ketentuan Pasal 340 KUHP dinyatakan:
Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
Di luar dua ketentuan di atas juga terdapat ketentuan lain yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku euthanasia, yaitu ketentuan Pasal 356 (3) KUHP yang juga mengancam terhadap Penganiayaan yang dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan untuk dimakan atau diminum.Selain itu patut juga diperhatikan adanya ketentuan dalam Bab XV KUHP khususnya Pasal 304 dan Pasal 306 (2). Dalam ketentuan Pasal 304 KUHP.
Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
Sementara dalam ketentuan Pasal 306 (2) KUHP dinyatakan, Jika mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dikenakan pidana penjara maksimal sembilan tahun.Dua ketentuan terakhir tersebut di atas memberikan penegasan, bahwa dalam konteks hukum positif di Indonesia, meninggalkan orang yang perlu ditolong juga dikualifikasi sebagai tindak pidana. Dua pasal terakhir ini juga bermakna melarang terjadinya euthanasia pasif yang sering terjadi di Indonesia.
Fenomena euthanasia ini berkembang lagi ketika kasus Nyonya Agian mencuat di permukaan ketika suaminya (Hasan) meminta DPRD Bogor untuk mengagalkan keinginannya untuk meng-eutanasia istrinya tersebut. Banyak orang yang menentang apa yang dilakukan Hasan pada istrinya tersebut,dengan alasan bahwa eutanasia itu bertentangan dengan nilai-nilai etika, moral karena termasuk perbuatan yang merendahkan martabat manusia dan perbuatannya tergolong pembunuhan, mengingat kematian menjadi tujuan.Sebuah karangan berjudul "The Slippery Slope of Dutch Euthanasia" dalam majalah Human Life International Special Report Nomor 67, November 1998, halaman 3 melaporkan bahwa sejak tahun 1994 setiap dokter di Belanda dimungkinkan melakukan euthanasia dan tidak akan dituntut di pengadilan asalkan mengikuti beberapa prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur tersebut adalah mengadakan konsultasi dengan rekan sejawat (tidak harus seorang spesialis) dan membuat laporan dengan menjawab sekitar 50 pertanyaan. kapankah hal seperti itu terjadi di Indonesia?Kiranya persoalan euthanasia, meskipun pelaksanaannya tidak harus dan tidak selalu dengan suntikan, merupakan sebuah persoalan dilematis. Selain hukum, praktik eutanasia tentu saja berbenturan dengan nilai-nilai etika dan moral yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kehidupan manusia. Adanya indikasi-indikasi baik medis maupun ekonomis tidak secara otomatis melegitimasi praktik eutanasia mengingat eutanasia berhadapan dengan faham nilai menyangkut hak dan kewajiban menghormati dan membela kehidupan.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Mengingat kondisi demikian, yang dibutuhkan kemudian adalah perawatan dan pendampingan, baik bagi si pasien maupun bagi pihak keluarga. Perhatian dan kasih sayang sangat diperlukan bagi penderita sakit terminal, bukan lagi bagi kebutuhan fisik, tetapi lebih pada kebutuhan psikis dan emosional, sehingga baik secara langsung maupun tidak kita dapat membantu si pasien menyelesaikan persoalan-persoalan pribadinya dan kemudian hari siap menerima kematian penuh penyerahan kepada penyelenggaraan Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimanapun si pasien adalah manusia yang masih hidup, maka perlakuan yang seharusnya adalah perlakuan yang manusiawi kepadanya.Jelas bahwa hukum (pidana) positif di Indonesia belum memberikan ruang bagi euthanasia baik euthanasia aktif maupun euthanasia pasif. Tanpa harus mengesampingkan pendapat lain, kesimpulan normatif ini urgen untuk disampaikan mengingat berbagai hal. Pertama, munculnya permintaan tindakan medis euthanasia hakikatnya menjadi indikasi, betapa masyarakat sedang mengalami pergeseran nilai kultural. Penulis menentang dilakukannya euthanasia atas dasar etika, agama, moral dan legal, dan juga dengan pandangan bahwa apabila dilegalisir, euthanasia dapat disalahgunakan. Kelompok pro-euthanasia mungkin akan menentang pendapat ini dengan menggunakan argumen quality of life, autonomi dan inkonsistensi hukum. Namun demikian, argumen-argumen yang telah dikemukakan di atas lebih kuat. Argumen pertama yaitu secara etika, tugas seorang dokter adalah untuk menyembuhkan, bukan membunuh; untuk mempertahankan hidup, bukan untuk mengakhirinya. Dasar agama adalah argumen berikutnya, di mana dokter percaya kesucian dan kemuliaan kehidupan manusia. Dari segi respek moral, pilihan untuk membunuh, baik orang lain maupun diri sendiri adalah imoral karena merupakan tindak sengaja untuk membunuh seorang manusia. Dari segi legal, seorang dokter yang melakukan euthanasia atau membantu orang yang bunuh diri telah melakukan tindakan melanggar hukum. Argumen terakhir adalah sulitnya untuk melegalisir euthanasia karena sulitnya membuat standar prosedur yang efektif. Lebih jauh lagi, melegalisir voluntary euthanasia dapat mengarah kepada dilakukannya involuntary euthanasia dan membuat orang-orang lemah seperti orang lanjut usia dan para cacat berada dalam risiko. Selanjutnya hal ini juga dapat memberikan tekanan kepada mereka yang merasa diabaikan atau merasa sebagai beban keluarga atau teman. Pengalaman di negeri Belanda telah membuktikan konsep slippery slope.
B. Saran
Apabila hukum di Indonesia kelak mau menjadikan persoalan eutanasia sebagai salah satu materi pembahasan, semoga tetap diperhatikan dan dipertimbangkan sisi nilai-nilainya, baik sosial, etika, maupun moral.
DAFTAR PUSTAKA
Wibudi, Aris, Euthanasia.(makalah) http://rudyct.tripod.com/sem2_012/aris_wibudi. ITB. Bogor. 2002Terbarzana, Rina Rehulina, Euthanasia. http://www.myquran.org/. 09 Agustus 2005
The Slippery Slope of Dutch Euthanasia. Human Life International Special Report Nomor 67, November 1998.
Kristiantoro, Amb Sigit, Eutanasia, Perspektif Moral Hidup.http://www.kompas.com/kompas-cetak/0410/15/ilpeng/1325806.htm Jumat, 15 Oktober 2004
Qardhawi, Yusuf, Fatwa-fatwa Kontemporer . Gema Insani Press.
Huston Smith. The Religion of Man (Agama agama Manusia). Diterjemahkan oleh Yayasan Obor Indonesia.
What happens after death?. http://folk.uio.no/mostarke/forens_ent/afterdeath.shtml. 21 April 2002
Glossary of Terms Concerning End of Life issues . http : // www .finalexit.org/glossframe.html 21 April 2002
Prakoso, Djoko dkk. 1984. Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. Ghalia Indonesia.
Petrus Yoyo Karyadi. 2001. Euthanasia dalam Perspektif Hak Azasi Manuisa. Media Prssindo.
PAGE 7