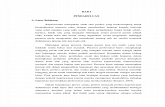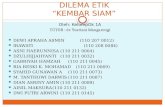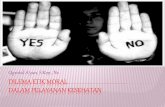Dilema Revitalisasi Pusaka Budaya
Transcript of Dilema Revitalisasi Pusaka Budaya
1
Dilema Revitalisasi Pusaka Budaya:Kasus Pembangunan Braga City Walk di Kota Bandung
Oleh: Sugeng P. Syahrie
AbstrakPada dua dasawarsa awal abad ke-20, Jl. Braga di Kota Bandung merupakan pusat perniagaanmodern yang sangat populer. Namun, pascakeme rdekaan kawasan Braga mengalamikemunduran aktivitas perdagangan sehingga daya tariknya memudar. Sebagai solusi, PemerintahKota Bandung membuat kebijakan revitalisasi perniagaan kawasan Braga dengan cara, antaralain, menggandeng pihak swasta untuk memban gun Braga City Walk (BCW) agar kawasan itumenjadi destinasi wisata belanja. Artikel ini mengajukan pandangan bahwa proses revitalisasikawasan bersejarah Jl. Braga dilakukan pemerintah setempat melalui proses pembangunan yangberwatak kapitalistik. Proses ini dapat menyebabkan kawasan tersebut mengalami komodifikasiyang mengancam signifikansi budayanya sebagai sebuah pusaka budaya.
Kata kunci: Jalan Braga, pusaka budaya, revitalisasi, komodifikasi, signifikansi budaya
AbstractIn the begining of 20th century, Jl. Braga in Bandung was knowns as a very popular modern tradecenter. But, after the independence, trading activities in Braga area was decl ined that resulted on thefading of its attraction. To solve the problem, local government made a policy to revitalize tradingactivities. Local goverment made a cooperation with private institutions to build Braga City Walk(BCW). The aim of the cooperation was to awaken Braga area as a shopping tourism destination. Thisarticle proposes an idea that the revita lization process of historical Braga area has been conducted bylocal government through capitalistic development processes. These processes has been impacted oncommodification that threaten cultural signification of Braga area as a cultural heritage.
Key words: Braga Street, cultural heritage, revitalization, commodification, cultural signification
1. PendahuluanBraga adalah nama sebuah jalan di Kota Bandung yang sudah sangat populer baik diIndonesia maupun di masyarakat internasional. Di masa lalu, pada periode 1920-1940-an ketika Indonesia masih di bawah kolonialisme Belanda, Jalan (Jl.) Braga merupakanpusat perniagaan modern yang hanya menjajakan barang -barang berkelas padazamannya, pusat interaksi sosial masyarakat Eropa , dan tempat berakulturas inya budayaEropa dengan lokal. Didirkan di situ berbagai bangunan berlanggam arsitektur Eropa,dari klasik-romantik, art deco, hingga Indo-European yang kemudian menjadi salah satupenanda identitas Kota Bandung.
Pascakemerdekaan kawasan Braga mengalami kemunduran aktivitas perdagangansehingga daya tariknya menjadi pudar. Menurut hasil kajian Budiman (2002), hal initerjadi terutama sejak kemunculan pusat perbelanjaan modern pada tahun 1980-an. padasiang hari aktivitas di kawasan ini semakin menurun. Beberapa bangunan terbengkalaidan beralih fungsi menjadi tempat hiburan malam. Alhasil, kawasan ini mengalamipenurunan citra budaya, sejarah, serta estetika lingkungan. Selain disebabkan olehkemampuan bersaing yang rendah karena banyak kawasan pertokoan lain yang munculdengan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang lebih baik dan modem , faktor-faktor lainnya adalah soal kenyamanan dan keleluasaan bagi pengunjung terutama pejalan
2
kaki, baik oleh karena padatnya arus lalu lintas, sarana parkir yang seadanya dan kondisitrotoar untuk pejalan kaki yang minim.
Agar kawasan Braga dapat hidup kembali, berbagai gagasan dalam menata kembalikawasan itu telah diajukan. Sudah berbagai cara dilakukan Pemerintah Kota B andunguntuk mengembalikan kawasan Jl. Braga ke kejayaan masa lalunya. 1 Akan tetapi, Bragamasih saja sepi. Braga kini menjadi kawasan yang sama sekali terpinggirkan dari maraknyapembangunan Kota Bandung. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandungkemudian membuat kebijakan revitalisasi 2 kawasan tersebut. Kebijakan ini, sebagaimanadicatat oleh Budiman (2002), didasari oleh konsep yang dikemukakan oleh Thomas Klaasyang bertujuan menjadikan kawasan Braga sebagai pusat perbelanjaan yang dikhususkanbagi pejalan kaki (pedestrian mall). Pemkot berharap bahwa revitalisasi kawasan Braga dapatmenghidupkan kembali aktivitas perniagaan dan menjadikan kawasan itu sebagai destinasiwisata belanja di Kota Bandung. Dalam konteks itulah Pemkot kemudian mendukungpembangunan Braga City Walk (BCW) oleh kalangan swasta.
Namun demikian, kita umumnya sepakat bahwa kawasan Braga adalah artefakbudaya yang patut dilindungi sehingga proses revitalisasinya harus taat pada kaidah-kaidahkonservasi3 atau pelestarian. Menurut Piagam Burra (lihat international.icomos.org, 1999),untuk melestarikan suatu tempat, harus ter lebih dahulu didefinisikan “signifikansibudaya” (cultural significance) tempat tersebut.4 Signifikansi budaya ini (lihat Thamrin,2008; lihat juga international.icomos.org, 1999) tersirat dalam tempat itu sendiri ini dandapat berupa bahan-bahannya, tata letaknya, fungsinya, asosiasinya, atau maknasimboliknya. Dalam upaya konservasi, perubahan tidak dilarang sepanjang—sebagaimanadinyatakan oleh Piagam—dilakukan sebanyak yang diperlukan tetapi membatasinyasesedikit mungkin.
Dengan demikian, dalam konteks revitalisasi Braga, seluruh upaya menghidupkankembali vitalitas ekonomi dan fisik kawasan J l. Braga hendaklah sesedikit mungkinmengubah keunikan atau signifikansi budaya yang hendak dilestarikan. Namun, disinilah problematikanya: pembangunan BCW itu dikhawatirkan oleh sebagian kalangandapat merusak “signifikansi budaya” yang telah ada. Artikel ini mengajukan pandanganbahwa proses revitalisasi kawasan bersejarah Jl. Braga dilakukan pemerintah mela luiproses pembangunan yang berwatak kapitalistik yang dapat menyebabkan kawasan inimengalami komodifikasi yang mengancam eksistensinya sebagai sebuah pusaka budaya(cultural heritage).
1 Tentang berbagai gagasan dan cara yang dilakukan dalam menata kembali Jalan Braga , lihatpernyataan Soediono (Pikiran Rakyat, 2004b), Ketua Paguyuban Braga. Sumber lain, lihat pernyataanKatam (detikbandung.com, 2008c) yang menjelaskan bahwa revitalisasi Braga dirintis sejak tahun 60 -anmelalui Braga Festival. Namun, baru tiga tahun berjalan, upaya ini selanjutnya terhenti. Pada 1980 -an,revitalisasi kembali digaungkan. Kawasan Braga kala itu digunakan sebagai arena Pameran Produksi JawaBarat, tetapi lagi-lagi tak berlanjut. Selanjutnya, pada tahun 90 -an sempat dicoba penggelaran eventbertajuk “Braga Kaget”. Ini pun kembali tak membuahkan hasil .
2 Revitalisasi didefinisikan sebagai proses untuk meningkatkan kegiatan sosial dan ekonomibangunan/lingkungan bersejarah, yang sudah kehilangan vitalitas aslinya. Lihat bandungheritage.org (tt).
3 Konservasi didefinisikan sebagai proses yang bertujuan memperpanjang umur warisan budayabersejarah, dengan cara memelihara dan melindungi keotentikan dan maknanya dari gangguan dankerusakan, agar dapat dipergunakan pada saat sekarang maupun masa yang akan datang, baik denganmenghidupkan kembali fungsi lama atau dengan memperkenalkan fungsi baru yang dibutuhkan. Lihatbandungheritage.org (2008).
4 Piagam Burra (Burra Charter) ialah Piagam ICOMOS (International Council on Monuments andSites) Australia untuk pelestaria n tempat bersignifikansi budaya . Tentang konsep “signifikansi budaya”ini, lihat Hall dan McArthur (1996).
3
2. Keniscayaan Revitalisasi Braga : Berbagai PandanganJl. Braga, yang dulunya menjadi pusat kehidupan budaya Kota Bandung tetapi kinimenjadi kawasan yang terpinggirkan itu, adalah sebuah produk sosiokultural yang dalampandangan banyak pihak harus direvitalisasi. Berbagai kalangan itu menyepakati hal inikarena menimbang nilai historis dan juga lokasi Braga yang strategis di tengah kota.
Pemkot Bandung berpandangan bahwa revitalisasi kawasan Braga akan dapatmenghidupkan kembali aktivitas perniagaan di Braga dan diharapkan dapat menjadi salahsatu tujuan wisata belanja di Kota Bandung. Namun, revitalisasi itu diharapkan tidakhanya menghidupkan kembali sentra bisnis di sepanjang Jl. Braga, tetapi juga memicuproses urban renewal untuk meningkatkan taraf hidup warga sekitarnya, khususnya dibagian belakang yang mengarah ke Sungai Cikapundung (Kompas, 2004b). Itu sebabnyaPemkot, sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Bappeda Kota Bandung (ibid), kemudianmendukung pembangunan BCW yang dikerjakan oleh pengembang swasta.
Menurut hasil observasi Pemkot, banyak pemilik ingin menghid upkan kembaliperekonomiannya, tetapi tidak bisa berbuat banyak, sehingga dibiarkan sebagaibangunan tua. Padahal, kawasan ini dianggap memiliki nilai jual karena nilaiarsitekturnya (parijsvanjava.com, 2008). Oleh sebab itu, untuk mewujudkan proyekBCW ini Pemkot memfokuskan revitalisasi pada penataan jalan, trotoar (diperlebar dikedua sisi untuk pejalan kaki), bangunan wall garden di gang-gang, lahan parkir, sertamenyelenggarakan berbagai festival di Jl. Braga (newspaper.pikiran-rakyat.co.id, 2008).Sedangkan revitalisasi gedung adalah kewajiban para pemilik atau pengelola gedung(Seputar Indonesia, 2008).
Di sisi lain, pihak pengembang properti juga memiliki pandangan yang sejalan denganPemkot, bahwa merevitalisasi kawasan Braga berarti menghidupkan kembali sebuahkawasan elite perniagaan yang pernah menjadi ikon penting Kota Bandung.5 Bahkan, bagimereka, isu pokok tentang Braga adalah semata soal revitalisasi kawasan bisnis. Dalamnalar ini, kesuksesan proses revitalisasi itu mereka serahkan pada meka nisme pasar.Mereka berpendapat bahwa keterlibatan pengembang hanya sampai pada menyediakan“gula bagi semut”. Artinya, begitu proyek awal yang menjadi pemicu (baca: BCW)dibangun, para pemilik modal diharapkan secara otomati s akan mau berinvestasi di Jl.Braga. Keterlibatan mereka sebagai pengembang diyakini akan dapat menghidupkankembali kawasan bersejarah Braga. Harapan itu, menurut mereka, cukup beralasan karenakeberadaan sebuah bangunan dengan 18 lantai yang dilengkapi menara kembar (twintower) akan menarik banyak pengunjung. Dengan demikian, bangunan -bangunan mati disepanjang Jalan Braga akan hidup kembali dengan sendirinya. 6
Namun, bagi kalangan akademisi, substansi revitalisasi itu lebih bermakna kulturaldaripada sekadar ekonomik. Richard Ho, pr ofessor pada Departement of Architectur,National University of Singapore, yang pernah melakukan riset terhadap kawasan Bragapada 2003 bersama Panguyuban Pelestarian Budaya Bandung (Bandung HeritageSociety—BHS) pernah mengatakan bahwa kondisi Braga yang merupakan pusatkehidupan budaya Kota Bandung kini tidak tampak lagi. Kini Braga tidak lagimemperlihatkan karakternya sebagai pusat kota, tidak sebanding dengan nilai -nilai yangtelah menjadi image masyarakat internasional. Maka, menurutnya, sudah saatnya
5 Lihat wawancara dengan Hadi Satyagraha , Management Advisor Agung Podomoro Group(perusahaan induk dari PT BMM yang menjadi investor pembangunan BCW), dalam proyeksi.com(2006).
6 Lihat pernyataan advisor proyek BCW Harry S. Soedarsono (Kompas, 2004a).
4
komponen yang peduli terhadap heritage dan arsitektur yang indah di Jl. Braga menatakembali lansekap kawasan ini secara fisik maupun sosiokultural, serta menghidupkanperekonomiannya. Ini adalah langkah untuk kembali mengangkat martabat KotaBandung serta nilai-nilai sejarah yang dikandungnya. 7 Himbauan Prof. Ho inisebenarnya sekedar mengkonfirmasi apa yang sebelumnya sudah sering diserukan olehbanyak akademisi dan praktisi lokal yang tergabung dalam wadah BHS.
Para penggiat BHS menilai bahwa karena tuj uan dari revitalisasi Braga menyangkutkepentingan masyarakat, masyarakat sekitar harus dilibatkan sejak awal. Selain itu,revitalisasi kawasan Braga juga memerlukan grand design yang tertata rapi. Dalammenentukan grand design tersebut, masyarakat perlu mengetahui arah kebijakan pemerintahagar tidak terjadi benturan yang dikhawatirkan menimbulkan gesekan antara pemerintahdengan masyarakat. Jadi, masyarakat mengerti langkah -langkah yang diambil pemerintahsekaligus bisa memberi masukan bagaimana baiknya. Setelah proses revitalisasi kawasanBraga selesai, keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam mendukung programpemerintah tidak serta-merta selesai. Pemerintah bisa memberdayakan masyarakat dalamproses menghidupkan kembali kejayaan kawasan tersebut (seputar-indonesia.com, tt).
Oleh sebab itu, ketika muncul rencana pembangunan BCW yang akanmerevitalisasi kawasan Braga dengan membangun hotel, apartemen, fasiltas komersial,fasilitas parkir dan open plaza, dengan tetap menjaga aspek lingkungan di seputar Braga —di tengah persoalan Braga yang begitu kompleks —para penggiat BHS menyambutnyadengan tangan terbuka. Mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukan pihakpengembang merupakan sesuatu yang baik karena dimaksudkan untuk menghidupkankembali kawasan Braga yang memang sudah mati. Tetapi, mereka juga mengingatkanbahwa gagasan pembangunan ini tentu tidak bisa dilakukan begitu saja tanpamempertimbangkan aspek lingkungan sosial di wilayah Braga tersebut, se perti kondisimasyarakat di bagian belakang Braga yang berdekatan dengan Sungai Cikapundung,juga kondisi pertokoan maupun kondisi jalan di Braga tersebut. 8
Dibangunnya mal, plaza, hotel atau apartemen tidak masalah asal tetap harusmemperhitungkan juga kondisi Braga secara menyeluruh. Artinya, pembangunan BCW inibisa berdampak lain. Misalnya, pengunjung hanya tersedot di tempat itu, sementarapertokoan lainnya tidak ada perubahan apa -apa. Demikian pula kondisi masyarakat dibelakang Braga, harus dipertimbangkan aspek sosialnya. 9
Di sisi lain, kalangan warga masyarakat Braga, baik masyarakat RW 08 di belakangJl. Braga maupun masyarakat pengusaha yang memiliki pertokoan di Braga, sudah sejaklama menginginkan adanya kebijakan pemerintah yang mendorong pe mberdayaankembali aktivitas di kawasan Jl. Braga agar dapat berperan sebagaimana pada masakejayaanya dulu. Oleh karena itu mereka menanggapi positif rencana pembangunanBCW asalkan pengembang mengakomodasi keinginan masyarakat agar tidak terjadikontradiksi antara pihak pengusaha dengan masyarakat . Terlebih di areal itu adaapartemen yang dihuni warga masyarakat baru. BCW mereka harapkan benar-benardapat menghidupkan kembali Braga yang sudah mati sekaligus memberi kesempatankepada mereka untuk meningkatkan kesejahteraannya.10
7 Lihat pernyataan Richard Ho (Pikiran Rakyat, 2004).8 Lihat pernyataan Ketua BHS Tuty Harastoety ( Pikiran Rakyat, 2004).9 Ibid.10 Lihat, pernyataan salah seorang tokoh masyarakat B raga di RW 08, Imam Sadikin ( ibid).
5
Akan tetapi, lebih dari tiga tahun setelah ia dibangun, pada kenyataannya BCW takmampu berfungsi seperti tujuan pembangunannya. Mal dengan 18 lantai yangdilengkapi menara itu tidak sanggup penyedot wisatawan lokal dan asing untukmengunjungi kawasan yang dulu sangat tersohor itu. Apalagi, untuk menghidupkan lagibangunan-bangunan berarsitektur art deco yang telah mati. Jl. Braga tetap saja sepipengunjung (newspaper.pikiran-rakyat.co.id, 2008). “Tadinya kami berharap BCWmampu mendongkrak perekonomian di Jl. Braga. Namun, rupanya tak sesuai harapan.BCW sendiri pun tak banyak menarik pengunjung ,” demikian pernyataan Kepala DinasTata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) Kota Bandung mengomentari kondisi Bragatersebut.11
3. Dilema: Ekonomik atau Kultural?Revitalisasi kawasan Braga sebenarnya sudah dilakukan Pemkot Bandung sejak tahun2000. Konsepnya adalah menjadikan Jl. Braga sebagai pusat perbelanjaan yang nyaman.Akan tetapi, Pemkot selama ini hanya menyentuh kulitnya saja. Program -programnyamasih sebatas perbaikan trotoar atau penanaman pohon. Tapi unsur -unsur ekonomidan komunitasnya tidak tersentuh. Agar revitalisasi Braga tak hanya menyentuh unsurfisik jalan, pengembalian fungsi Jl. Braga sebagai pusat per niagaan kemudian dilakukanoleh Pemkot dengan cara melibatkan dan menyokong para pengusaha untuk berniaga disana.12 Upaya ini membuahkan hasil pada 2003 ketika dimulai pembangunan BCWoleh sebuah pengembang swasta .13 Tujuannya adalah untuk membangkitkan perniagaanyang saat itu telah redup di jalan tersebut melalui pembangunan gedung pertokoan ritelyang merangkap hotel dan apartemen (konsep mixed use retail dan hunian).
Sebagaimana dikonsepsikan oleh Pemkot Bandung, BCW juga dikonsepkan olehpihak pengembang sebagai pemantik g eliat ekonomi di sekitar Jl. Braga. Dengan sejumlahpertimbangan, baik faktor historis maupun faktor-faktor mutakhir seperti pertambahanpenduduk, perubahan gaya hidup, pertumbuhan ekonomi Kota yang sangat baik, danindustri pariwisata yang tumbuh pesat , mereka menilai bahwa pembangunan BCW adalahtepat karena selaras dengan kecenderungan mutakhir dalam industri properti komersial,yakni pembangunan lifestyle center.14 Ini semua meyakinkan mereka bahwa potensi pasar diKota Bandung—walaupun tidak sebesar Jakarta—adalah luar biasa (proyeksi.com, 2006).
Dari sisi ekonomi, lifestyle center memang lebih menguntungkan karena membidiksegmen pasar menengah ke atas dan memiliki target yang spesifik yakni kelompokmasyarakat berpendapatan tinggi (high disposable income groups), keluarga muda, dan kaumeksekutif. Konsep lifestyle center terbukti sukses menggaet pengunjung. Ini seperti yangdiprediksi oleh Victor Gruen dalam Shopping Towns USA: The Planning of Shopping Center(1960, dalam Anonim, 2007) bahwa pusat perbelanjaan yang akan merebut pasar di masadepan adalah yang mampu menyediakan lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhanberbelanja dan menawarkan kelebihan pada sisi sosial, rekreasional, dan hiburan.
11 Lihat pernyataan Juniarso Ridwan, Kepala Distarcip Kota Bandung ( ibid).12 Ibid.13 Pengembang (developer)-nya adalah PT Bangun Mitra Mandiri (BMM), anak perusahaan Grup Agung
Podomoro. Mereka menginvestasikan dana sejumlah Rp 350 -an miliar pada proyek BCW itu. Lihat SinarHarapan, 2004).
14 Lifestyle center adalah gaya arsitektur berdesain terbuka atau se mi terbuka (open-air mall) denganmemperbanyak ruang-ruang bersama yang dapat digunakan untuk aktivitas sosial pengunjungnya. LihatAnonim (2007)
6
Selain dari perspektif industri properti komersial , pembangunan BCW juga sejalandengan tema mutakhir dalam penataan kota. Dalam beberapa tahun terakhir ini, sepertidilaporkan oleh wartawan Kompas Winarto Herusansono (2006), sejumlah kota sedangberlomba membuat proyek city walk. Dalam perkembangannya, city walk ternyata sangatmendorong peningkatan pendapatan pajak dan menciptakan lapangan kerja baru disuatu kota. Di Yogyakarta, proyek city walk yang masih digarap serius adalah kawasanMalioboro, yang sangat terkenal di kalangan turis lokal dan mancanegara. SedangkanPemerintah Kota Solo mengembangkan kawasan city walk di sepanjang Jl. Slamet Riyadi.Konsep kawasan city walk ini biasanya mencakup area penuh plaza terbuka, pusatperbelanjaan, apartemen, hotel, dan perkantoran. Di sini warga bisa leluasa jalan ditrotoar maupun sebagian jalan, atau sekedar bercengkerama dengan keluarga, bebas darideru dan debu kendaraan.
Namun demikian, seperti dinyatakan oleh pengamat tata kota dari InstitutTeknologi Bandung Widjaja Martokusumo (2004), dalam wacana akademik desainperkotaan dipostulasikan bahwa perkembangan kota dan modernisasi telahmengantarkan keseragaman wajah kota dan lenyapnya lokalitas. Dengan dalihpembangunan, kawasan kota lama akan mudah menja di sasaran empuk para investor.Dengan kecenderungan seperti in i, budaya membangun pun mengalami defisiensidialog nalar karena kekuatan masyarakat tidak tercermin dalam karya, kecuali kekuasaanpragmatis pasar. Begitu kuatnya hegemoni pasar hingga mengakibatkan persoalan wajahbangunan dan citra lingkungan tidak lebi h dari sekadar ”tampak saja” dan bentukanmonolitik. Sebagai akibat, kota-kota di Indonesia tidak memiliki karakter yang kuat.Kini sejumlah besar wajah kota besar dan menengah di Indonesia mulai hilangkekhasannya. Jakarta menjadi prototype pertumbuhan kota-kota di Indonesia lainnya:semerawut, penuh dengan ruko, dan tidak aksesibel . Lebih memprihatinkan lagi, h inggakini masih banyak pemerintah kota/daerah yang menganggap warisan sejarah tersebutsebagai penghalang bagi pembangunan.
Dari paparan mengenai kecenderungan mutakhir dalam industri properti dankonsep penataan kota, serta tinjauan kritis wacana akademik desain perkotaan, dapatdisimpulkan bahwa program revitalisasi kawasan Braga melalui proyek BCW adalahterlalu sarat dengan kepentingan ekonomik sehingga mengabaikan kepentingankonservasi pada aspek signifikansi budayanya. Itu sebabnya mengapa proyek BCWkemudian memunculkan resistensi dari kalangan BHS dan Paguyuban Braga yangumumnya adalah para pemilik toko di sepanjang jalan itu. Mereka menilai bahwakonsep BCW bersifat parsial sehingga justru dapat mengancam hilangnya gaya arsitekturkuno serta karakter bangunan-bangunannya, berpotensi mematikan toko -toko disepanjang jalan itu, dan akhirnya dapat merusak citra J l. Braga sebagai kawasankonservasi sejarah budaya. Menurut mereka, konsep BCW tidak akan berhasil jikahanya dilakukan secara parsial. Seharusnya Pemkot mengajak semua pihak, baik ituwarga, LSM, pengusaha (pemiliki toko) di Braga, untuk merumuskan bersama skenariobesar untuk revitalisasi Braga ini (lihat Kompas, 2004a dan 2004c; dan Aldrin, 2007).
Pembangunan BCW juga mengundang reaksi dari warga masyarakat yang tinggal disekitarnya. Warga yang rumahnya langsung berbatasan dengan gedung hotel danapartemen setinggi 18 lantai merasa t erganggu.karena rumah mereka tertutup bayangangedung sehingga tidak mendapat sinar Matahari. Mereka mengeluhkan tidak adanyapihak pengembang yang bersedia berdialog dengan warga. Padahal, menurut dia, barumembangun sumur untuk proyek saja sudah cukup bi sing hingga menggangguketenteraman warga (Kompas, 2004a). Ketika pembangunan BCW sudah berlalu satu
7
tahun, kenyataannya, seperti dilaporkan oleh detikbandung.com (2008b), belum terlihatdampak positif dari kehadiran BCW pada keberadaan dan revitalisa si bangunan-bangunan bersejarah. Geliat kehidupan perniagaan Jl. Braga yang dulu sering di gembar-gemborkan oleh pihak pengembang justru berakibat tertutupnya kawasan Braga utaraoleh papan reklame. Tentu, selain berakibat kemacetan, hal ini juga mengakibatkanpenyempitan ruas jalan dan pemakaian jalan sebagai area parkir al ternatif. Sementara,kemilau kehidupan malam yang terkesan mesum di Jl. Braga tetap eksis seperti kalabelum dibangun BCW
Sedangkan harapan Pemkot Bandung perihal terjadinya proses urban renewal untukmeningkatkan taraf hidup warga sekitar Jl. Braga kini hanya menjelma menjadi mimpi(lihat Kompas, 2006). Masyarakat mulai mengeluh bahwa air susah karena sumur keringdan udara pengap. Air leding yang kuning hanya menetes pada siang hari , dan barupada malam hari aliran air cukup besar. Di tengah malam warga masih beraktivitasuntuk mencuci perkakas dapur atau mencuci pakaian. Karena hanya ada sekitar limaMCK di kampung itu, warga memanfaatkan gang sempit di muka atau di sampingrumah untuk tempat mencuci piring. Karena tidak semua gang dilengkapi saluranlimbah rumah tangga, air pun menggenang di mana -mana dan menjadi sarang nyamukAedes aegypti. Setiap tahun, ada saja warga yang menderita demam berdarah.
Menanggapi munculnya berbagai keluhan dan resistensi dari banyak kalanganmasyarakat tersebut, pihak pengembang BCW berupaya mengatasinya dengan menjalinkomunikasi yang lebih baik dengan warga sekitar. Mereka juga membantu pembangunansarana-sarana MCK bagi warga sekitar dan rehabilitasi Jl. Braga. Mereka menilai bahwapersoalan tersebut muncul karena warga kawasan Braga belum sepenuhnya memahamiarti penting dan manfaat proyek BCW. Sebab itu, kepada warga yang tidak menyukaikehadiran BCW, mereka berupaya memberi penjelasan berulang kali. Dalam bentuk yanglebih konkret, mereka juga mempekerjakan warga sekitar di BCW, antara lain sebagaipetugas pengamanan profesional dan pramuniaga. Hal lain yang mereka anggap sebagaikontribasi sosial pengembang adalah efek multiplier positif dari BCW ini terhadap wargasekitar berupa meningkatnya harga tanah (lihat proyeksi.com, 2006). Merespons keluhanwarga soal kesulitan air, pengembang juga membangun sumur -sumur air tanah baru.Dengan demikian maka penggunaan air tanah untuk kepentingan BCW tidak akanmengganggu air tanah yang dipergunakan oleh masyarakat sekitar. 15 Selain itu, merekajuga membuka akses jalan ke arah perumahan warga di belakang gedung BCW. Denganini, menurut mereka, kehidupan warga otomatis akan dapat terbangun juga. Bagi mereka,ini adalah perwujudan dari kaidah proses pembangunan partisipatif dari investor .16
Sejalan dengan pandangan pengembang, kalangan legislatif Kota Bandung jugamenekankan pentingnya masyarakat (khususnya warga Braga) mengetahui danmemahami tujuan pembangunan yang yang dilakukan pemerintah. Ini berguna agarprogram yang dijalankan pemerintah bisa diperkuat oleh masyarakat sehinggapemerintah dengan masyarakat bisa bahu -membahu.
Pembangunan kawasan Braga harus disosialisasikan dulu sehingga masyarakat bisa memahamiapa tujuan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Pemahaman ini penting agar masyarakatturut memiliki program yang dijalankan pemerintah. 17
15 Lihat pernyataan Direktur PT BMM (pengembang BCW) Tjen Ruddy Chandra (Sinar Harapan,2004).
16 Lihat pernyataan Penasihat PT BMM Harry S. Soedarsono ( Kompas, 2004b).17 Lihat pernyataan Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Arif Ramdhan (seputar-indonesia.com,
2008).
8
Sedangkan pihak Pemkot menggaransi bahwa bangunan -bangunan bersejarah yangakan dibenahi tetap akan dipertahankan esen si artistiknya, dan untuk untuk merekabekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Mengenai dampak pembangunanBCW yang dikeluhkan banyak kalangan masyarakat, mereka berpendirian bahwa apayang dilakukan pemerintah (bersama kalangan pengembang swas ta) itu baru tahappermulaan sehingga masyarakat perlu bersabar sampai melihat hasilnya secarakeseluruhan nanti. Program revitalisasi Braga ini direncanakan bertahap dan tidakterbatas pada pembenahan jalan , tapi juga bangunan tua hingga kawasan pemukimankumuh dan Sungai Cikapundung yang melintas di kawasan itu .18
Mencermati apa yang dilakukan oleh pengembang BCW dan pemerintah dalammengatasi munculnya resistensi sosial, tampak bahwa nalar kapitalisme ekonomi dengansegenap “dogma” keuntungan finansial secepat mungkin memang hampir selalu tidakseiring dengan nalar humanisme kultural. Dalam kasus Braga, persoalannya adalahbahwa tidak semua pihak yang berkepentingan memandang modal historis dan kulturalkeindahan kota yang telah dimiliki itu sebagai sebuah produk sosiokultural yang harusdikonservasi. Alhasil, harapan akan kembali hidup dan tumbuhnya aktivitas sosial -ekonomi di kawasan Jl. Braga secara keseluruhan seiring dengan dibangunnya BCWkemudian tinggal menjadi harapan belaka, masih jauh dari kenyat aan(parijsvanjava.com, 2008). Ongkos besar kultural pembangunan BCW berupapenghancuran toko dan bengkel Mercedes tertua di Hindia, tempat orang -orangIndonesia di masa lalu belajar otomotif (Republika, 2008), tidak membuat Braga semakinramai. Braga tetap sepi. Bahkan, Festival Braga ketiga yang digelar pada 29-31 Desember2007 merupakan yang tersepi. Bila dua Festival Braga sebelumnya dihadiri puluhan ribuorang, festival ketiga yang bertema Mabaraga hanya dihadiri ribuan orang (ibid). BCW,yang saat akan dibangun bervisi -misi merevitalisasi kawasan Braga , dalam kenyataannyakemudian hadir lebih hanya demi melayani kepentingan bisnisnya sendiri, bukan untukrevitalisasi kawasan Braga sebagai pusaka budaya.
Apakah kedua nalar (kapitalisme ekonomi dan humanisme kultural) yang berbedakepentingan itu tidak bisa dipertemukan? Selama ini konservasi kawasan bersejarah ataucagar budaya memang selalu dipertentangkan dengan upaya -upaya pembangunan kotayang lebih berorientasi komersial. Padahal, s ejatinya di sana masih tersisa ruang yangtidak saling menegasikan satu sama lain. Keuntungan ekonomi sebetulnya bisa munculdari kerja keras pemegang otoritas untuk mempertahankan otentisitas wajah kotanya.Kuncinya—meminjam pernyataan Guru Besar Antropologi Universitas P adjadjaran,Bandung, Prof. Dr. Kusnaka Adimihardja (Pikiran Rakyat, 2004a)—jangan melihatsesuatu dari keuntungan finansial jangka pendek ( tangible). Artinya, bila warisan budayadikelola dengan tepat maka akan memberikan topangan kesejahteraan, bukan cumapada sisi budaya, tetapi juga sisi ekonomi, wisata, dan sistem sosial yang terpelihara.
4. KesimpulanKasus ini memperlihatkan bahwa ada perbedaan nalar atau nilai di antara para pihakyang terlibat dalam proyek BCW sehingga pembangunannya tidak membawa manfaatmeluas, malah menimbulkan potensi konflik sosial. Berbagai kalangan masyarakat itutampaknya memiliki penilaian bahwa proses revitalisasi kawasan bersejarah Jl. Braga inidilakukan pemerintah melalui proses pembangunan yang berwatak kapitalistik ya ng
18 Lihat pernyataan Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandu ng, Rusyaf Adimanggala (detikbandung.com,2008a).
9
dapat menyebabkan kawasan ini mengalami komodifikasi 19 yang mengancam culturalheritage (pusaka budaya).20 Sedangkan kapitalisme melanggengkan hegemoni. Dalamkonteks ini, Pemkot Bandung menjalankan politik ekonomi instan yang mengorbankanpusaka budaya sehingga kawasan Jl. Braga terancam mengalami proses komodifikasi.Sementara, pada sisi lain, sejumlah kalangan masyarakat justru peduli dengan persoalankonservasi khazanah pusaka budaya. Makna konservasi pusaka budaya ini sebenarnyaterkait dengan tuntutan hak budaya (cultural rights), baik untuk konservasi itu sendirimaupun dalam kaitannya dengan manfaatnya bagi kehidupan dan kesejahteraanmasyarakat. Upaya konservasi pusaka budaya merupakan perjuangan hak budaya dankepentingan praksis emansipasi masyar akat Kota Bandung.
Adanya resistensi sosial yang kemudian tidak dapat diatasi sampai tuntas dalam kasusini, menunjukkan bahwa ada persoalan yang menghambat kemungkinkan dicapainyapartisipasi yang demokratis (democratic participation) dalam pengelolaan proyek BCW.Dalam wacana akademik teori -teori sosial, akar persoalan ini bisa dijelaskan denganmerujuk pada watak kapitalistik yang dianut oleh Pemkot Bandung sebagai inisiatorproyek BCW maupun—terlebih lagi—oleh pengembang. Sedangkan secara praksis,tampaknya masyarakat tidak sepenuhnya dapat mengetahui dan memahami arahkebijakan pemerintah sekaligus terhambatnya akses bagi mereka untuk memberi masukandan terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai bagaimana baiknyarevitalisasi kawasan Braga harus dilakukan. Padahal, dalam demokrasi (lihat, Urovsky, tt),pemerintah seharusnya, sebisa mungkin, bersikap terbuka —yang artinya, gagasan dankeputusan yang dibuat harus terbuka bagi pengujian publik secara seksama .
Paradoks dari kasus adalah bahwa wata k kapitalistik yang menyertai kasus iniadalah justru bersumber pada nilai -nilai kebebasan (freedom) individual yang menjadiprinsip dasar sistem ekonomi pasar.
Market economy ... rest upon the fundamental principle of individual freedom: freedom as a c onsumerto choose amon competing products and services; freedom as a producer to start or expand a businessand share its risks and rewards; freedom as a worker to choose a job or career, join a labor union orchange employers.21
Padahal, sering dikatakan bahwa tidak ada demokrasi dalam masyarakat tan pa adanyakebebasan individul. Bahwa, dalam kasus ini, kebebasan individual (yang termuat dalamsistem pasar yang berwatak kapitalistik itu), yang dianggap oleh sebagian kalanganmasyarakat menyertai proses pem bangunan BCW, justru pada akhirnya menerbitkanancaman bagi dicapainya partisipasi yang demokratis oleh publik awam, hal ini sekadarmenegaskan (kembali) bahwa sampai hari ini pun demokrasi masih harus terus berjuanguntuk mengelola kontradiksi -kontrdiksi internal yang dikandungnya.
Sebagai penutup kesimpulan ini, saya hendak mengetengahkan (kembali) pendapat—yang sebenarnya sudah sering disuarakan oleh para ahli perencanaan dan perancangankota kita—bahwa tantangan pokok yang dihadapi dalam revitalisasi su atu kawasanbersejarah adalah bagaimana pengelolaannya dapat merupakan bagian dari rencanapengembangan kota berkelanjutan. Tantangan ini, tentu saja, sangat berat mengingat
19 Komodifikasi adalah proses yang diasosiasikan dengan kapitalisme di mana objek, kualitas, dantanda dijadikan sebagai komoditas dan komoditas adalah sesuatu yang tujuan utamanya untuk dijual dipasar. Lihat, Chris Barker (2005).
20 Cultural heritage di sini saya definisikan sebagai sumber daya budaya yang memiliki signifikansibudaya, yaitu memiliki berbagai nilai dan makna secara ilmu pengetahuan, ekonomik, estetik , dansimbolik
21 Lihat Michael Watts (1992).
10
pemerintah pada umumnya tidak punya mekanisme perihal bagaimana seharusnya sebuahrencana pembangunan kawasan bersejarah harus dilaksanakan. Dapat dikatakan di sinibahwa sebagian besar kota di Indonesia sangat tertinggal dalam sistem pen gelolaan danpersepsi terhadap pusaka budaya masyarakat, baik yang tangible maupun intangible. Persepsitentang apa itu heritage pun masih belum sinkron di antara berbagai pihak terkait ,terutama kalangan akademisi, aktivis pelestarian pusaka budaya, dan pemerintah (lihatindonesiapusaka.org, 2004). Padahal, ini sangat penting supaya pemerintah dapatmembuat kebijakan dan menyusun program konservasi yang bermanfaat untuk jangkapanjang.
Betapapun, masih terdapat pelajaran yang bisa dipetik dari kasus ini: bahwaorientasi yang terlalu kuat pada kepentingan ekonomik dalam kebijakan revitalisasikawasan bersejarah dapat mengakibatkan kepentingan konservasi sering terlupakan.Gagalnya konservasi kawasan bersejarah, demikian dikatakan oleh para pakar sejarahdan konservasi arsitektur (lihat Antariksa, 2007), akan dapat menimbulkan erosiidentitas budaya dan sejarah kota atau kawasan yang kemudian dapat berakibat lebihjauh: generasi–generasi mendatang tidak dapat lagi melihat mata ra ntai sejarah tempattinggalnya.[]
Daftar PustakaAnonim. 2007. “Bandung Indah Plaza: Ikon Bandung yang Terjebak Perubahan Jaman”
(http://shallypristine.wordpress.com/2007 /10/14/bandung-indah-plaza-ikon-bandung-yang-terjebak-perubahan-jaman/<diakses 9/9/2008>).
Antariksa. 2007. “Pelestarian Bangunan Kuno Sebagai Aset Seja rah Budaya Bangsa”Pidato pengukuhan jabatan guru besar dalam bidang ilmu sejarah dan pelestarianarsitektur pada Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, 3 Desember 2007(http://antariksaarticle.blogspot.com/2007/12/pelestarian -bangunan-kuno-sebagai-aset.html <diakses 9/9/2008>).
bandungheritage.org. tt [tanpa tanggal] . ”Prinsip Utama Kegiatan Konservasi”,(http://bandungheritage.org/ <diakses 14/9/2008>).
Barker, Chris. 2005. Cultural Studies, Teori dan Praktik . Terjemahan Nurhadi . Yogyakarta:Bentang Pustaka.
Budiman, Budi Irsan. 2002. ”Kajian Konsep Pedestrian Mall di Kawasan KonservasiBraga”, tesis magister, Institut Teknologi Bandung.
detikbandung.com. 2008a. “Anggaran Revitalisasi Braga Hampir Rp 2 Miliar”,(http://bandung.detik.com/read/2008/01/30/141246/886599/486/tv/index.html<diakses 11/9/2008>).
detikbandung.com. 2008b. “Bangunan Belanda di Braga Hanya Tersisa 73 Persen”(http://bandung.detik.com/readfotodetail/2008/01/31/124302/887000/486/0/tv/ <diakses 11/9/2008>).
detikbandung.com. 2008c. “Hikayat Revitalisasi Braga yang Selalu Gagal ”(http://bandung.detik.com/read/2008/01/30/161 425/886601/486/tv/index.html<diakses 11/9/2008>)
Hall, Michael dan Simon McArthur (editor). 1996, Heritage Management in Australia andNew Zealand. Melbourne: Oxford University Press.
Herusansono, Winarto. 2006. “Seandainya Kota Semarang Punya ‘City Walk’ ”, Kompas,24 Februari.
11
indonesiapusaka.org, 2004. “Kota di Indonesia Belum Punya Persepsi tentang ‘Heritage’”(http://www.indonesiapusaka.org/mt3/archives/ta hun_pusaka_indonesia_2003/index.html <diakses 11/9/2008>).
international.icomos.org . 1999. “Piagam Burra”. Terjemahan Rika Susanto & Hastitarekat. http://www.international.icomos.org/charters/burra1999_indonesian.pdf
Kompas. 2004a. “Mengembalikan Kejayaan Jalan Braga”, 6 Mei.Kompas. 2004b. ”Pemkot Harapkan BCW Tingkatkan Taraf Hidup Masyarakat”, 6 Mei.Kompas. 2004c. “Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya demi Asas Manfaat”, 27 Juli.Kompas. 2006. “Braga, Turis Pun Kini Meringis”, 27 Februari.Martokusumo, Widjaja. 2004. “Desain Urban dan Konservasi Kawasan Kota Tua
Jakarta“, Kompas, 3 Oktober.newspaper.pikiran-rakyat.co.id. 2008. “Merindukan Braga yang Cantik dan Nyaman”,
(http://newspaper.pikiran-rakyat.co.id/prprint.php?mib=beritadetail&id=16003<diakses 11/9/2008>).
parijsvanjava.com. 2008. “Jalan Braga Akan Dijadikan Weekend Market”(http://naryo.net/parijsvanjava.com_2008/index.php?o ption=com_content&task=view&id=16&Itemid=1&date=2009 -12-01 <diakses 11/9/2008>).
Pikiran Rakyat. 2004a. “Memudarnya Wajah ‘Eropa di Surga Tropis’”, 23 Maret.Pikiran Rakyat. 2004b. “Menggosok ”Permata Kota” yang Pudar”, 19 Juli.proyeksi.com. 2006. “Kelebihan Agung Podomoro Group di Eksekusinya”
http://www.proyeksi.com/berita/desain/0190906_braga.htm <diakses 11/9/2008>).Republika. 2008. ”Jalan Braga: Hidup Segan, Mati tak Mau”, Republika, 4 Januari.Seputar Indonesia. 2008. “Revitalisasi Braga Setengah Hati”, 30 Agust us.seputar-indonesia.com. tt [tanpa tanggal]. “Masyarakat Harus Dilibatkan” (www.seputar-
indonesia.com <diakses 14/9/2008>).Sinar Harapan. 2004. “Pembangunan Braga City Walk Tunggu Amdal ”, 4 [Mei?].Thamrin, Muhammad. 2008. “Menutup Braga dengan Andesit. Tepatkah?” Republika 1
September.Urovsky, Melvin J. tt [tanpa tahun]. “Naskah Pertama: Prinsip -prinsip Dasar Pertama”,
dalam George Clack (redaktur eksekutif), Demokrasi. Office of InternationalInformation Programs, U.S. Department of State.
Watts, Michael. 1992, What is a Market Economy? Office of International InformationPrograms, U.S. Department of State.
Biodata penulisSugeng P. Syahrie mengajar di Jurusan Sejarah UNJ dala m mata kuliah Sejarah Indonesia MasaKlasik dan Sejarah Sains dan Teknologi. Setelah menamatkan pendidikan s arjananya di JurusanArkeologi Universitas Indonesia (1998), ia kemudian mengembangkan minatnya pada studi sains,teknologi, dan masyarakat (science, technology and society studies) di Institut Teknologi Bandung (ITB)sejak 2007. Publikasinya, antara lain, adalah “Dari ‘exotic theory’ hingga neo -Marxis: jalan panjangpencarian model asal -mula produksi pangan” (Cakrawala Arkeologi, Jurusan Arkeologi UniversitasIndonesia, 2003); “Teknologi, Demokrasi, dan Pembelajaran Sosial: ‘Lesson Learned’ dari KasusRencana Pembangunan PLTN Muria” ( Sosialita, Jurnal Sosial Pendidikan , Vol. 6 No. 1, Desember2009). Ia menyunting sejumlah buku, antara lain Peradaban Jawa: Dinamika Pranata Pol itik, Agama,Ekonomi Jawa Kuna (Komunitas Bambu, 2002); (bersama Adi Nusferadi) The Holocaust Industry (Ufuk,2006); Impian dari Tepi Kali Cibogo: Otobiografi Hadi Soebadio (Pramita Press, 2007), dan A YoungJavanese Shepherd Finding Indonesia in the Kanga roo Land (Pramita Press, 2009). Saat ini ia sedangmelakukan riset teoretik di bidang teknokultur (technoculture) serta aplikasinya pada bidang kajian