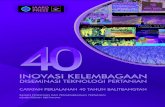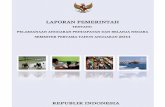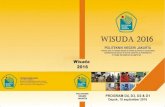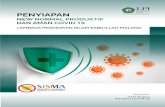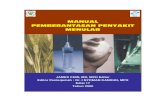daftar isi
-
Upload
pesanroket -
Category
Documents
-
view
213 -
download
1
description
Transcript of daftar isi
BAB IPENDAHULUAN1. 1 Latar BelakangBatubara merupakan batuan sedimen non klastik yang mengandung unsur-unsur Carbon (C), Hidrogen (H), Oksigen (O) dan Nitrogen (N) yang digunakan sebagai bahan bakar dunia. Batubara terbentuk melalui dua tahapan yaitu proses penggambutan dan coalifikasi. Pada proses pembentukan batubara terdapat proses sedimentasi bersamaan mineral lain seperti pirit, gypsum, silica, markasit ataupun anhidrit yang dapat menyebabkan terjadinya pengotor batubara. Pengotor batubara tidak hanya terjadi pada saat pembentukan batubara namun juga pada saat proses penambangan sehingga batubara tercampur dengan material lain. Pemboran dilakukan untuk mengambil conto batubara dilapangan. Dari hasil pemboran tersebut didapatkan sebuah log bor yang dimana mengambakan litologi batuan dari lubang bor satu dengan yang lainnya sehingga dapat dikorelasikan dan diketahui sebaran dari batubara dan lapisannya. Dari data yang didapat maka dibuatlah sebuah profil melintang yang bertujuan untuk mengetahui keadaan, lokasi dan gambaran tentang topografi didaerah pengeboran.Berdasarkan latar belakang inilah penyusun membuat laporan mengenai pembuatan penampang dan log bor.1. 2 Rumusan MasalahYang menjadi topik permasalahan dalam penyusunan laporan ini :1. Bagaimana menginterpretasikan penampang berdasarkan pada pata lokasi Bor Hole ?2. Bagaimana menginterpretasikan log bor berdasarkan data Bor Hole pada pata lokasi Bor Hole ?3. Bagaimana menginterpretasikan korelasi log bor dalam penampang berdasarkan data Bor Hole pada pata lokasi ?1. 3 TujuanAdapun tujuan dari pembuatan laporan ini :1. Dapat menginterpretasikan penampang berdasarkan pada pata lokasi Bor Hole.2. Dapat menginterpretasikan log bor berdasarkan data Bor Hole pada pata lokasi Bor Hole.3. Dapat menginterpretasikan korelasi log bor dalam penampang berdasarkan data Bor Hole pada pata lokasi.1. 4 ManfaatAdapun manfaat dari pembuatan laporan ini :1. Mengetahui bagaimana menginterpretasikan penampang berdasarkan pada pata lokasi Bor Hole.2. Mengetahui bagaimana menginterpretasikan log bor berdasarkan data Bor Hole pada pata lokasi Bor Hole.3. Mengetahui bagaimana korelasi log bor dalam penampang berdasarkan data Bor Hole pada pata lokasi.
BAB IIDASAR TEORI
2.1 Batubara
Gambar 2.1 BatubaraBatubara merupakan salah satu sumber daya alam yang keberadaanya melimpah di Indonesia. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Geologi, Kementerian ESDM tahun 2009, total sumber daya batubara yang dimiliki Indonesia mencapai 104.940 Milyar Ton dengan total cadangan sebesar 21.13 Milyar Ton. Batubara merupakan sedimen organik, lebih tepatnya merupakan batuan organik, terdiri dari kandungan bermacam-macam pseudomineral. Batubara terbentuk dari sisa tumbuhan yang membusuk dan terkumpul dalam suatu daerah dengan kondisi banyak air, biasa disebut rawa-rawa. Kondisi tersebut yang menghambat penguraian menyeluruh dari sisa-sisa tumbuhan yang kemudian mengalami proses perubahan menjadi batubara.2.1.1 Pengenalan BatubaraSelain tumbuhan yang ditemukan bermacam-macam, tingkat kematangan juga bervariasi, karena dipengaruhi oleh kondisi-kondisi lokal. Kondisi lokal ini biasanya kandungan oksigen, tingkat keasaman, dan kehadiran mikroba. Pada umumnya sisa-sisa tanaman tersebut dapat berupa pepohonan, ganggang, lumut, bunga, serta tumbuhan yang biasa hidup di rawa-rawa. Ditemukannya jenis flora yang terdapat pada sebuah lapisan batubara tergantung pada kondisi iklim setempat. Dalam suatu cebakan yang sama, sifat-sifat analitik yang ditemukan dapat berbeda, selain karena tumbuhan asalnya yang mungkin berbeda, juga karena banyaknya reaksi kimia yang mempengaruhi kematangan suatu batubara.Secara umum, setelah sisa tanaman tersebut terkumpul dalam suatu kondisi tertentu yang mendukung (banyak air), pembentukan dari peat (gambut) umumnya terjadi. Dalam hal ini peat tidak dimasukkan sebagai golongan batubara, namun terbentuknya peat merupakan tahap awal dari terbentuknya batubara. Proses pembentukan batubara sendiri secara singkat dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan dari sisa-sisa tumbuhan yang ada, mulai dari pembentukan peat (peatifikasi) kemudian lignit dan menjadi berbagai macam tingkat batubara, disebut juga sebagai proses coalifikasi, yang kemudian berubah menjadi antrasit. Pembentukan batubara ini sangat menentukan kualitas batubara, dimana proses yang berlangsung selain melibatkan metamorfosis dari sisa tumbuhan, juga tergantung pada keadaan pada waktu geologi tersebut dan kondisi lokal seperti iklim dan tekanan. Jadi pembentukan batubara berlangsung dengan penimbunan akumulasi dari sisa tumbuhan yang mengakibatkan perubahan seperti pengayaan unsur karbon, alterasi, pengurangan kandungan air, dalam tahap awal pengaruh dari mikroorganisme juga memegang peranan yang sangat penting.2.1.2 Pengertian BatubaraBatubara adalah bahan bakar fosil. Batubara dapat terbakar, terbentuk dari endapan, batuan organik yang terutama terdiri dari karbon, hidrogen dan oksigen. Batubara terbentuk dari tumbuhan yang telah terkonsolidasi antara strata batuan lainnya dan diubah oleh kombinasi pengaruh tekanan dan panas selama jutaan tahun sehingga membentuk lapisan batubara.2.1.3 Pembentukan BatubaraKomposisi batubara hampir sama dengan komposisi kimia jaringan tumbuhan, keduanya mengandung unsur utama yang terdiri dari unsur C, H, O, N, S, P. Hal ini dapat dipahami, karena batubara terbentuk dari jaringan tumbuhan yang telah mengalami coalification. Pada dasarnya pembentukkan batubara sama dengan cara manusia membuat arang dari kayu, perbedaannya, arang kayu dapat dibuat sebagai hasil rekayasa dan inovasi manusia, selama jangka waktu yang pendek, sedang batubara terbentuk oleh proses alam, selama jangka waktu ratusan hingga ribuan tahun. Karena batubara terbentuk oleh proses alam, maka banyak parameter yang berpengaruh pada pembentukan batubara. Makin tinggi intensitas parameter yang berpengaruh makin tinggi mutu batubara yang terbentuk.Ada dua teori yang menjelaskan terbentuknya batubara, yaitu teori insitu dan teori drift. Teori insitu menjelaskan, tempat dimana batubara terbentuk sama dengan tempat terjadinya coalification dan sama pula dengan tempat dimana tumbuhan tersebut berkembang.Teori drift menjelaskan, bahwa endapan batubara yang terdapat pada cekungan sedimen berasal dari tempat lain. Bahan pembentuk batubara mengalami proses transportasi, sortasi dan terakumulasi pada suatu cekungan sedimen. Perbedaan kualitas batubara dapat diketahui melalui stratigrafi lapisan. Hal ini mudah dimengerti karena selama terjadi proses transportasi yang berkaitan dengan kekuatan air, air yang besar akan menghanyutkan pohon yang besar, sedangkan saat arus air mengecil akan menghanyutkan bagian pohon yang lebih kecil (ranting dan daun). Penyebaran batubara dengan teori drift memungkinkan, tergantung dari luasnya cekungan sedimentasi.Pada proses pembentukan batubara atau coalification terjadi proses kimia dan fisika, yang kemudian akan mengubah bahan dasar dari batubara yaitu selulosa menjadi lignit, subbitumina, bitumina atau antrasit.
Gambar 2.2 Jenis Jenis BatubaraDari tinjauan beberapa senyawa dan unsur yang terbentuk pada saat proses coalification (proses pembatubaraan), maka dapat dikenal beberapa jenis batubara yaitu:1. Antrasit(C94OH3O3) adalah kelas batu bara tertinggi, dengan warna hitam berkilauan (luster) metalik, mengandung antara 86% 98% unsurkarbon(C) dengan kadar air kurang dari 8%. Dengan sifat :- Warna hitam mengkilap- Material terkompaksi dengan kuat- Mempunyai kandungan air rendah- Mempunyai kandungan karbon padat tinggi- Mempunyai kandungan karbon terbang rendah- Relatif sulit teroksidasi- Nilai panas yang dihasilkan tinggi.
2.Bituminus(C80OH5O15) mengandung 68 86% unsurkarbon(C) dan berkadar air 8-10% dari beratnya.Dengan sifat :-Warna hitam- Material sudah terkompaksi-Mempunyai kandungan air sedang-Mempunyai kandungan karbon padat sedang- Mempunyai kandungan karbon terbang sedang-Sifat oksidasi rnenengah-Nilai panas yang dihasilkan sedang.3.Sub-bituminus(C75OH5O20),mengandungsedikitkarbondan banyak air, dan oleh karenanya menjadi sumber panas yang kurang efisien dibandingkan dengan bituminus. Sifat dari sub-bituminus mempunya kesamaan dengan bitumus, yaitu :-Warna hitam- Material sudah terkompaksi-Mempunyai kandungan air sedang-Mempunyai kandungan karbon padat sedang- Mempunyai kandungan karbon terbang sedang-Sifat oksidasi rnenengah-Nilai panas yang dihasilkan sedang.4.Lignit(C70OH5O25) atau batu bara coklat adalah batu bara yang sangat lunak yang mengandung air 35-75% dari beratnya. Dengan sifat :-Warna kecoklatan-Material terkornpaksi namun sangat rapuh- Mempunyai kandungan air yang tinggi-Mempunyai kandungan karbon padat rendah-Mempunyai kandungan karbon terbang tinggi-Mudah teroksidasi- Nilai panas yang dihasilkan rendah.5.Gambut (C60H6O34), berpori dan memiliki kadar air di atas 75% serta nilai kalori yang paling rendah. Dengan sifat :-Warna coklat-Material belum terkompaksi-Mernpunyai kandungan air yang sangat tinggi-Mempunvai kandungan karbon padat sangat rendah-Mempunyal kandungan karbon terbang sangat tinggi-Sangat mudah teroksidasi-Nilai panas yang dihasilkan amat rendah.2.1.4 Faktor yang Mempengaruhi Proses Pembentukan BatubaraAda tiga faktor yang mempengaruhi proses pembetukan batubara yaitu: umur, suhu dan tekanan.Mutu endapan batubara juga ditentukan oleh suhu, tekanan serta lama waktu pembentukan, yang disebut sebagai maturitas organik. Pembentukan batubara dimulai sejak periode pembentukan Karbon (Carboniferous Period) dikenal sebagai zaman batubara pertama yang berlangsung antara 360 juta sampai 290 juta tahun yang lalu. Proses awalnya, endapan tumbuhan berubah menjadi gambut/peat (C60H6O34) yang selanjutnya berubah menjadi batubara muda (lignite) atau disebut pula batubara coklat (brown coal). Batubara muda adalah batubara dengan jenis maturitas organik rendah. Setelah mendapat pengaruh suhu dan tekanan secara continue selama jutaan tahun, maka batubara muda akan mengalami perubahan yang secara bertahap menambah maturitas organiknya dan mengubah batubara muda menjadi batubara sub-bituminus (sub-bituminous). Perubahan kimiawi dan fisika terus berlangsung sampai batubara menjadi lebih keras dan warnanya lebih hitam sehingga membentuk bituminus (bituminous) atau antrasit (anthracite). Dalam kondisi yang tepat, peningkatan maturitas organik yang semakin tinggi terus berlangsung hingga membentuk antrasit.Maturitas organik sebenarnya menggambarkan perubahan konsentrasi dari setiap unsur utama pembentuk batubara, dalam proses pembatubaraan. Sementara itu semakin tinggi peringkat batubara, maka kadar karbon akan meningkat, sedangkan hidrogen dan oksigen akan berkurang. Disebabkan tingkat pembatubaraan secara umum dapat diasosiasikan dengan mutu atau mutu batubara, batubara bermutu rendah yaitu batubara dengan tingkat pembatubaraan rendah seperti lignite dan sub-bituminus biasanya lebih lembut dengan materi yang rapuh dan berwarna suram seperti tanah, memiliki tingkat kelembaban (moisture) yang tinggi dan kadar karbon yang rendah, sehingga kandungan energinya juga rendah. Semakin tinggi mutu batubara, umumnya akan semakin keras dan kompak, serta warnanya akan semakin hitam mengkilat. Selain itu, kelembabannya pun akan berkurang sedangkan kadar karbonnya akan meningkat, sehingga kandungan energinya juga semakin besar.2.1.5 Kualitas BatubaraBatubara yang diperoleh dari hasil penambangan mengandung bahan pengotor (impurities). Hal ini bisa terjadi ketika proses coalification (pembentukan batubara) ataupun pada proses penambangan yang dalam hal ini menggunakan alat-alat berat yang selalu bergelimang dengan tanah. Ada dua jenis pengotor, yaitu:1. Inherent impuritiesMerupakan pengotor bawaan yang terdapat dalam batubara. Batubara yang sudah dibakar memberikan sisa abu. Pengotor bawaan ini terjadi bersama-sama pada proses pembentukan batubara. Pengotor tersebut dapat berupa gybsum (CaSO42H2O), anhidrit (CaSO4), pirit (FeS2), silica (SiO2). Pengotor ini tidak mungkin dihilangkan sama sekali, tetapi dapat dikurangi dengan melakukan pembersihan.2. Eksternal impuritiesMerupakan pengotor yang berasal dari uar, timbul pada saat proses penambangan antara lain terbawanya tanah yang berasal dari lapisan penutup.Sebagai bahan baku pembangkit energi yang dimanfaatkan industri, mutu batubara mempunyai peranan sangat penting dalam memilih peralatan yang akan dipergunakan dan pemeliharaan alat. Dalam menentukan kualitas batubara perlu diperhatikan beberapa hal antara lain :a.Heating Value (HV) (calorific value/Nilai kalori)Banyaknya jumlah kalori yang dihasilkan oleh batubara tiap satuan berat dinyatakan dalam kkal/kg. Semakin tinggi HV, makin lambat jalannya batubara yang diumpankan sebagai bahan bakar setiap jamnya, sehingga kecepatan umpan batubara perlu diperhatikan. Hal ini perlu diperhatikan agar panas yang ditimbulkan tidak melebihi panas yang diperlukan dalam proses industri.b. Moisture Content (kandungan lengas)Lengas batubara ditentukan oleh jumlah kandungan air yang terdapat dalam batubara. Kandungan air dalam batubara dapat berbentuk air internal (air senyawa/unsur), yaitu air yang terikat secara kimiawi. Jenis air ini sulit dihilangkan tetapi dapat dikurangi dengan cara memperkecil ukuran butir batubara. Jenis air yang kedua adalah air eksternal, yaitu air yang menempel pada permukaan butir batubara.Batubara mempunyai sifat hidrofobik yaitu ketika batubara dikeringkan, maka batubara tersebut sulit menyerap air, sehingga tidak akan menambah jumlah air internal.c. Ash content (kandungan abu)Komposisi batubara bersifat heterogen, terdiri dari unsur organik dan senyawa anorgani, yang merupakan hasil rombakan batuan yang ada di sekitarnya, bercampur selama proses transportasi, sedimentasi dan proses pembatubaraan. Abu hasil dari pembakaran batubara ini, yang dikenal sebagai ash content. Abu ini merupakan kumpulan dari bahan-bahan pembentuk batubara yang tidak dapat terbaka atau yang dioksidasi oleh oksigen. Bahan sisa dalam bentuk padatan ini antara lain senyawa SiO2, Al2O3, TiO3, Mn3O4, CaO, Fe2O3, MgO, K2O, Na2O, P2O, SO3, dan oksida unsur lain.d. Sulfur Content (Kandungan Sulfur)Belerang yang terdapat dalam batubara dibedakan menjadi 2 yaitu dalam bentuk senyawa organik dan anorganik. Belerang dalam bentuk anorganik dapat dijumpai dalam bentuk pirit (FeS2), markasit (FeS2), atau dalam bentuk sulfat. Mineral pirit dan malkasit sangat umum terbentuk pada kondisi sedimentasi rawa (reduktif). Belerang organik terbentuk selama terjadinya proses coalification. Adanya kandungan sulfur, baik dalam bentuk organik maupun anorganik di atmosfer dipicu oleh keberadaan air hujan, mengakibatkan terbentuk air asam. Air asam ini dapat merusak bangunan, tumbuhan dan biota lainnya.2.1.6 Pemanfaatan BatubaraBatubara merupakan sumber energi dari bahan alam yang tidak akan membusuk, tidak mudah terurai berbentuk padat. Oleh karenanya rekayasa pemanfaatan batubara ke bentuk lain perlu dilakukan. Pemanfataan yang diketahui biasanya adalah sebagai sumber energi bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara, sebagai bahan bakar rumah tangga (pengganti minyak tanah) biasanya dibuat briket batubara, sebagai bahan bakar industri kecil; misalnya industri genteng/bata, industri keramik. Abu dari batubara juga dimanfaatkan sebagai bahan dasar sintesis zeolit, bahan baku semen, penyetabil tanah yang lembek. Penyusun beton untuk jalan dan bendungan, penimbun lahan bekas pertambangan,; recovery magnetit, cenosphere, dan karbon; bahan baku keramik, gelas, batu bata, dan refraktori; bahan penggosok (polisher); filler aspal, plastik, dan kertas; pengganti dan bahan baku semen; aditif dalam pengolahan limbah (waste stabilization).
Gambar 2.3 Pembangkit Listrik Tenaga UapAda beberapa faktor yang menadi alasan batubara digunakan sebagai sumber energi alternatif, yaitu:1. Cadangan batubara sangat banyak dan tersebar luas. Diperkirakan terdapat lebih dari 984 milyar ton cadangan batubara terbukti (proven coal reserves) di seluruh dunia yang tersebar di lebih dari 70 negara.2. Negara-negara maju dan negara-negara berkembang terkemuka memiliki banyak cadangan batubara.3. Batubara dapat diperoleh dari banyak sumber di pasar dunia dengan pasokan yang stabil.4. Harga batubara yang murah dibandingkan dengan minyak dan gas.5. Batubara aman untuk ditransportasikan dan disimpan.6. Batubara dapat ditumpuk di sekitar tambang, pembangkit listrik, atau lokasi sementara.7. Teknologi pembangkit listrik tenaga uap batubara sudah teruji dan handal.8. Kualitas batubara tidak banyak terpengaruh oleh cuaca maupun hujan.9. Pengaruh pemanfaatan batubara terhadap perubahan lingkungan sudah dipahami dan dipelajari secara luas, sehingga teknologi batubara bersih (clean coal technology) dapat dikembangkan dan diaplikasikan.2.1.7 Gasifikasi BatubaraGasifikasi batubara adalah sebuah proses untuk mengubah batubara padat menjadi gas batubara yang mudah terbakar (combustible gases), setelah proses pemurnian gas-gas karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO2), hidrogen (H), metan (CH4), dan nitrogen (N2) akhirnya dapat digunakan sebagai bahan bakar. Hanya menggunakan udara dan uap air sebagai reacting gas kemudian menghasilkan water gas atau coal gas, gasifikasi secara nyata mempunyai tingkat emisi udara, kotoran padat dan limbah terendah.Untuk melangsungkan gasifikasi diperlukan suatu suatu reaktor. Reaktor tersebut dikenal dengan nama gasifier. Ketika gasifikasi dilangsungkan, terjadi kontak antara bahan bakar dengan medium penggasifikasi di dalam gasifier. Kontak antara bahan bakar dengan medium tersebut menentukan jenis gasifier yang digunakan. Secara umum pengontakan bahan bakar dengan medium penggasifikasinya pada gasifier dibagi menjadi tiga jenis, yaitu entrained bed, fluidized bed, dan fixed/moving bed.2.2 Pemboran (Drilling)Pemboran adalah salah satu kegiatan penting dalam sebuah industri pertambangan. Kegiatan pemboran biasanya dilakukan sebelum diadakannya penambangan. Drilling string atau sering disebut rangkaian pemboran adalah serangkaian peralatan yang disususn sedemikian rupa, sehingga merupakan batang bor, seluruh peralatan ini mempunyai lubang dibagian dalamnya yang memungkinkan untuk melakukan sirkulasi fluida atau mud. Bagian ujung terbawah dari rangkaian pemboran adalah pahat bor atau bit yang gunanya untuk mengorek atau menggerus batuan, sehingga lubang bor bertambah dalam. Di atas pahat bor disambung dengan beberapa buah drill colar, yaitu pipa penyambung terdalam susunan rangkaian pemboran, untuk memungkinkan pencapain kedalaman tertentu, makin dalam lubang bor makin banyak jumlah drill pipe yang dibutuhkan. Diatas drill pipe disambung dengan pipa kelly, yang bertugas meneruskan gerakan dari rotary table untuk memutar seluruh rangkaian pemboran. Diatas kelly disambung dengan swivel yaitu sebuah alat yang berfungsi sebagai tempat perpindahan gerakan putar dan gerakan diam dari system sirkulasi , fluida pemboran melalui pipa bertekanan tinggi, bagian atas dari kelly ada bail untuk dikaitkan ke HOOk supaya memungkinkan turun seluruh rangkaian pemboran.
Gambar 2.4 PemboranPeralatan peralatan lain yang melengkapi susunan rangkaian pemboran :1. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemboran Bit sub adalah sub penyambung antara pahat dengan drill colar2. Float sub adalah sub penyambung yang dipsang bit sub dan drill colar, berfungsi untuk menutup semburan /tekanan formasi kedalam rangkaian pemboran secara otomatis.3. Stabilizer adalah alat yang dipasang pada susun drill colar, yang berfungsi untuk menstabilkan arah lubang bor dan mengurangi kemungkinan terjepitnya rangkaian pemboran yang diakibatkan oleh diferensial pressure.4. Kelly saver sub, adalah alat yang dipasang dibagian ujung bawah kelly, berfungsi untuk melindungi ulir kelly agar tidak cepat rusak.5. Lower kelly cock adalah alat yang dipasang antara kelly dan kelly saver sub, befungsi untuk alat penutup semburan /tekanan dari dalam pipa pada saat posisi kelly diatas Rotary Table.6. Upper Kely cock adalah alat yang dipasang diantara kelly dan swivel, berfunsi untuk menutup semburan/tekanan dari dalam pipa saat kelly down.Kinerja suatu mesin bor dipengaruhi oleh faktor-faktor sifat batuan yang dibor,rock drillability, geometri pemboran, umur dan kondisi mesin bor, dan ketrampilan operator.a. Sifat BatuanSifat batuan yang berpengaruh pada penetrasi dan sebagai konsekuensi pada pemilihan metode pemboran yaitu : kekerasan, kekuatan, elastisitas, plastisitas, abrasivitas, tekstur, struktur, dan karakteristik pembongkaran.1. KekerasanKekerasan adalah daya tahan permukaan batuan terhadap goresan. Batuan yang keras akan memerlukan energy yang besar untuk menghancurkanya. Pada umumnya batuan yang keras mempunyai kekuatan yang besar pula (Lihat table 2.1). Kekerasan batuan diklasifikasikan dengan skala Fredrich Van Mohs (1882).2. Kekuatan (strength)Kekuatan mekanik suatu batuan merupakan daya tahan batuan terhadap gaya dari luar, baik bersifat static maupun dinamik. Kekuatan batuan dipengaruhi oleh komposisi mineralnya, terutama kandungan kuarsa. Batuan yang kuat memerlukan energi yang besar untuk menghancurkanya.3. Bobot isi / Berat jenisBobot isi(density)batuan merupakan berat batuan per satuan volume. Batuan dengan bobot isi yang besar untuk membongkarnya memerlukan energy yang besar pula.4. Kecepatan Rambat Gelombang SeismikBatuan yang masif mempunyai kecepatan rambat gelombang yang besar. Pada umumnya batuan yang mempunyai kecepatan rambat gelombang yang besar akan mempunyai bobotisi dan kekuatan yang besar pula sehingga sangat mempengaruhi pemboran.5. AbrasivitasAbrasivitas adalah sifat batuan yang dapat digores oleh batuan lain yang lebih keras. Sifat ini dipengaruhi oleh kekerasan butiran batuan, bentuk butir, ukuran butir, porositas batuan, dan sifat heterogenitas batuan.6. TeksturTekstur batuan dipengaruhi oleh struktur butiran mineral yang menyusun batuan tersebut. Ukuran butir mempunyai pengaruh yang sama dengan bentuk batuan, porositas batuan, dan sifat-sifat batuan lainya. Semua aspek ini berpengaruh dalam keberhasilan operasi pemboran.7. ElastisitasSifat elastisitas batuan dinyatakan dengan modulus elastisitas atau modulus Young (E). Modulus elastisitas batuan bergantung pada komposisi mineral dan porositasnya. Umumnya batuan dengan elastisitas yang tinggi memerlukan energi yang besar untuk menghancurkanya.8. PlastisitasPlastisitas batuan merupakan perilaku batuan yang menyebabkan deformasi permanen setelah tegangan dikembalikan ke kondisi awal, dimana batuan tersebut belum hancur. Sifat ini sangat dipengaruhi oleh komposisi mineral penyusunya, terutama kuarsa. Batuan yang plastisitasnya tinggi memerlukan energi yang besar untuk menghancurkannya.9. Struktur GeologiStruktur geologi seperti sesar, kekar, dan bidang perlapisan akan berpengaruh terhadap peledakan batuan. Adanya rekaha-rekahan dan rongga-rongga di dalam massa batuan akan menyebabkan terganggunya perambatan gelombang energy akibat peledakan. Namun adanya rekahan-rekahan tersebut juga sangat menguntungkan untuk mengetahui bidang lemahnya, sehingga pemboran akan dilakukan berlawanan arah dengan bidang lemahnya.b. Drilabilitas Batuan (Drillability of Rock)Drilabilitas batuan adalah kecepatan penetrasi rata-rata mata bor terhadap batuan. Nilai drilabilitasini diperoleh dari hasil pengujian terhadap toughness berbagai tipe batuan oleh Sievers dan Furby. Hasil pengujian mereka memperlihatkan kesamaan nilaipenetration speeddannet penetration rateuntuk tipe batuan yang sejenis.c. Umur dan Kondisi Mesin BorAlat yang sudah lama digunakan biasanya dalam kegiatan pemboran, kemampuan mesin bor akan menurun sehingga sangat berpengaruh pada kecepatan pemboran. Umur mata bor dan batang bor ditentukan oleh meter kedalaman yang dicapai dalam melakukan pemboran. Untuk menilai kondisi suatu alat dapat dilakukan dengan mengetahui empat tingkat ketersediaan alat, yaitu:1. Ketersediaan Mekanik (Mechanical Availability, MA)Ketersediaan mekanik adalah suatu cara untuk mengetahui kondisi mekanik yang sesungguhnya dari alat yang digunakan. Kesediaan mekanik (MA) menunjukkan ketersediaan alat secara nyata karena adanya waktu akibat masalah mekanik. 2. Ketersediaan Fisik (Physical Availability, PA)Ketersediaan fisik menunjukkan kesiapan alat untuk beroperasi didalam seluruh waktu kerja yang tersedia.3. Penggunaan EfektifPenggunaan efektif menunjukkan berapa persen waktu yang dipergunakan oleh alat untuk beroperasi pada saat alat tersebut dapat digunakan. Penggunaan efektif sebenarnya sama dengan pengertian efisiensi kerja. 4. Pemakaian Ketersediaan (Use of Availability, UA)Ketersediaan Penggunaan menunjukkan berapa persen waktu yang dipergunakan oleh alat untuk beroperasi pada saat alat tersebut dapat digunakan. Penggunaan efektif EUsebenarnya sama dengan pengertian efisiensi kerja. Penilaian Ketersediaan alat bor dilakukan untuk mengetahui kondisi dan kemampuan alat bor untuk menyediakan lubang ledak. Kesediaan alat dikatakan sangat baik jika persen 90%, dikatakan sedang jika berkisar antara 70%-80%, dikatakan buruk (kecil) jika persen kesediaan alat70%.2.2.1 Tujuan PemboranTujuan dari kegiatan pemboran ini ada bermacam - macam, pemboran tidak saja dilakukan dalam industri pertambangan tetapi juga untuk bidang-bidang lain sehingga secara keseluruhan kegitan pemboran bertujuan sebagai berikut:1. Eksplorasi mineral dan batubara2. Ekplorasi dan produksi air tanah3. Eksplorasi dan produksi gas4. Eksplorasi dan produksi minyak5. Peledakan6. Geoteknik7. Ventilasi tambang8. Penirisan tambang9. Keperluan perhitungan cadangan10. Perolehan data geologi11. Pengontrolan tambang dan12. Serta pembuatan lubang pipa air untuk PDAM dan kabel listrik untuk PLN, dll2.2.2 Mesin BorBeberapa hal penting yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pemilihan mesin bor yang digunakan, diantaranya meliputi: Tipe/ model mesin bor Diameter lubang Sliding stroke Berat mesin bor Power unit Kemampuan rotasi/ tumbuk per satuan waktu Hoisting capacity (kapasitas) Dimensi (panjang x lebar x tinggi)
Didalam pemboran ada beberapa jenis mesin bor diantaranya adalahsebagaiberikut:1.MesinBorTumbuk2.MesinBorPutar3. Mesin Bor Putar Hidrolik2.2.2.1 Mesin Bor TumbukMesin bor tumbuk yang biasanya disebut cable tool atau spudder rig yang diopersikan dengan cara mengangkat dan menjatuhkan alat bor berat secara berulang- berulang ke dalam lubang bor. Mata bor akan memecahkan batuan terkosolidasi menjadi kepingan kecil,atau akan melepaskan butiran butiran pada lapisan.Kepingan atau hancuran tersebut merupakan campuran lumpur dan fragmen batuan pada bagian dasar lubang, jika di dalam lubang tidak dijumpai air, perlu ditambahkan air guna membentuk fragmen batuan (slurry).Pertambahan volume slurry sejalan dengan kemajuan pemboran yang pada jumlah terentu akan mengurangi daya tumbuk bor.Bila kecepatan laju pemboran sudah menjadi sangat menjadi sangat lambat, slurry diangkat ke permukaan dengan menggunakan timba (bailer) atau sand pump. Beberapa factor yang mempengaruhi kecepatan laju pemboran (penetrasi) dalam pemboran tumbuk diantaranya adalah : Kekerasan lapisan batuan Diameter kedalam lubang bor Jenis mata bor Kecepatan dan jarak tumbuk Beban pada alat borKapasitas mesin bor tunbuk sangat tergantung pada berat perangkat penumbuk yang merupakan fungsi dari diameter mata bor, diameter dan panjang drill-stemnya. Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan mesin bor tumbuk jika dibandingkan denngan mesin bor putardapatdijelaskansebagaiberikut:Kelebihannya:1. Ekonomis: - Harga lebih murah sehingga depresiasi lebih kecil- Biaya transportasi lebih murah- Biaya operasi dan pemeliharaannya lebih rendah- Penyiapan rig untuk pemboran lebih cepat2. Menghasilkaaan contoh pemboraan yang lebih baik3. Tanpa sistem sirkulasi.4. Lebih mempermudah pengenalan lokasi akifer5. Kemungkinan kontaminasi karena pemboran relative lebih kecil
Kekurangannya:1. Kecepatan laju pemboran rendah2. Sering terjadi sling putus3. Tidak bisa mendapatkan core4. Tidak memiliki saran pengontrol kestabilan lubang bor5. Terbatasnyaa personil yang berpengalaman6. Pada formasi yang mengalami swelling clay akan menghadapi banyak hambatan2.2.2.2 Mesin Bor PutarMesin bor putar merupakan jenis mesin bor yang mempuyai mekanisme yang paling sederhana, untuk memecahkan batuan menjadi kepingan kecil, mata bor hanya mengandalkan putaran mesin dan beban rangkaian stang bor. Jika pemboran dilakukan pada formasi batuan yang cukup keras, maka rangkain stang bor dapat ditambah dengan stang pemberat. Kepingan batuan yang hancur oleh gerusan mata bor akan terangkat ke permukaan karena dorongan fluida. Contoh yang populer dari jenis ini adalah meja putar dan elektro motor.Pada jenis meja putar, putaran vertical yang dihasilkan oleh mesin penggerak dirubah menjadi putaran horizontal oleh sebuah meja bulat yang ada pada bagian bawahnya terdapat alur alur yang berpola konsentris, sedangkan pada elektro motor, energi mekanik yang digunakan untuk memutar rangkaian stang bor berasal dari generator listrik yang dihubungkan pada sebuah elektro motor.Komponen komponen utama dari mesin bor putar adalah:1. Swivel2 Kelly bar3. Stabilizer4. Mata bor5. Stang bor6. Stang pemberat2.2.2.3 Mesin Bor Putar - HidrolikPada mesin bor putar hidrolik, pembebanan pada mata bor terutama diatur oleh sistem hidrolik yang terdapat pada unit mesin bor, disamping beban yang berasal dari berat stang bor dan mata bor. Cara kerja dari jenis mesin bor ini adala mengombinasikan tekanan hidrolik, stang bo dan putaran mata bor di atas formasi batuan.Formasi batuan yang tergerus akan terbawa oleh fluida bor ke permukaan melalui rongga anulus atau melalui rongga stang bor yang bergantung pada sistem sirkulasi fluida bor yang digunakan .Adapun contoh mesin bor putar hidrolik adalah:1. Top DriveUnit pemutar pada jenis Top Drive bergerak turun naik pada menara, tenaganya berasal dari unit transmisi hidrolik yang digerakkan oleh pompa.Penetrasinya dapat langsung sepanjang stang bor yang dipakai (umumnya sepanjang 3,6m 9 m), sehingga jenis mempuyai kinerja yang paling baik.2. SpindlePada jenis ini pemutarannya bersifat statis, kemajuan pemboran sangat dipengaruhi oleh panjang spindle (umumnya antara 60 m 100 m), dan tekanan hidrolik yang dibutuhkan.Adapun spesifikasi mesin bor yang digunakan adalah: Merk Kapasitas Berat Kemampuan rotasi Dimensi Diameter lubang Tipe/ model
2.3 Profil Melintang
Gambar 2.5 Profil MelintangTopografi merupakan gabungan kata topos yang berarti tempat dan graphi yang berarti menggambar yang berasal dari bahasa yunani kuno. Jadi, peta topografi berarti peta yang menggambarkan posisi mendatar dan posisi tegak dari semua benda yang membentuk atau berada di permukaan bumi. Isinya terdiri dari 4 ciri, yakni : relief (ketinggian), perairan (seperti Sungai danau), Tumbuhan ( Hutan ,semak, kelapa) dan hasil budaya manusia (jalan raya, bangunan, jembatan). Peta ini biasa disebut peta umum karena isinya yang lebih lengkap. Peta Topografi selalu dibagi dalam kotak-kotak untuk membantu menentukan posisi di peta dalam hitungan koordinat. Koordinat adalah kedudukan suatu titik pada peta. Secara teori, koordinat merupakan titik pertemuan antara absis dan ordinat. Koordinat ditentukan dengan menggunakan sistem sumbu, yakni perpotongan antara garis-garis yang tegak lurus satu sama lain. Peta adalah gambaran pada suatu permukaan datar dari seluruh atau sebagian dari permukaan bumi, untuk memperlihatkan kenampakan fisik, politik atau yang lainnya. Peta adalah penggambaran dua dimensi (pada bidang datar) dari sebagian atau keseluruhan permukaan bumi yang dilihat dari atas, kemudian diperbesar atau diperkecil dengan perbandingan tertentu. Dalam navigasi darat digunakan peta topografi. Peta ini memetakan tempat-tempat dipermukaan bumi yang berketinggian sama dari permukaan laut menjadi bentuk garis kontur.Dalam banyak kasus, penggambaran profil melintang (cross section) dari rute perjalanan mempunyai manfaat yang cukup besar, terutama untuk daerah yang belum pernah dikunjungi. Penggambaran penampang melintang bertujuan untuk memperlihatkan bentuk topografi dalam tiap segmen. Segmen disini diartikan sebagai titik ketinggian dan jarak. Pada ketinggian berapa keadaan topografi berlereng landai, terjal sampai sangat terjal dan beberapa derajat kemiringan lereng tiap segmen adalah salah satu contoh yang bisa diketahui dari penampang melintang. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pembuatan profil melintang :1. Tarik garis transis yang dikehendaki diatas peta, bisa berupa garis lurus maupun mengikuti rute perjalanan.2. Beri tanda (huruf atau angka) pada titik awal dan akhir3. Buat grafik pada milimeter blok untuk sumbu x dipakai sekala horizontal dan sumbu y sekala vertikal.4. Ukur pada peta jarak sebenarnya (jarak pada peta x angka penyebut skala peta) dan ketinggian (beda tinggi) pada jarak yang diukur tadi.5. Pindahkan setiap angka beda tinggi dan jarak sebenarnya tadi sebanyak-banyaknya pada grafik.6. Hubungkan setiap titik pada grafikPeta Topografi selalu dibagi dalam kotak-kotak untuk membantu menentukan posisi dipeta dalam hitungan koordinat. Koordinat adalah kedudukan suatu titik pada peta. Secara teori, koordinat merupakan titik pertemuan antara absis dan ordinat. Koordinat ditentukan dengan menggunakan sistem sumbu, yakni perpotongan antara garis-garis yang tegak lurus satu sama lain. Sistem koordinat yang resmi dipakai ada dua macam yaitu :1. Koordinat Geografis (Geographical Coordinate), Sumbu yang digunakan adalah garis bujur (bujur barat dan bujur timur) yang tegak lurus dengan garis khatulistiwa, dan garis lintang (lintang utara dan lintang selatan) yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Koordinat geografis dinyatakan dalam satuan derajat, menit dan detik. Pada peta Bakosurtanal, biasanya menggunakan koordinat geografis sebagai koordinat utama. Pada peta ini, satu kotak (atau sering disebut satu karvak) lebarnya adalah 3.7 cm. Pada skala 1:25.000, satu karvak sama dengan 30 detik (30"), dan pada peta skala 1:50.000, satu karvak sama dengan 1 menit (60").2. Koordinat Grid (Grid Coordinate atau UTM) dalam koordinat grid, kedudukan suatu titik dinyatakan dalam ukuran jarak setiap titik acuan. Untuk wilayah Indonesia, titik acuan berada disebelah barat Jakarta (60 LU, 980 BT). Garis vertikal diberi nomor urut dari selatan ke utara, sedangkan horizontal dari barat ke timur. Sistem koordinat mengenal penomoran 4 angka, 6 angka dan 8 angka. Pada peta AMS, biasanya menggunakan koordinat grid. Satu karvak sebanding dengan 2 cm. Karena itu untuk penentuan koordinat koordinat grid 4 angka, dapat langsung ditentukan. Penentuan koordinat grid 6 angka, satu karvak dibagi terlebih dahulu menjadi 10 bagian (per 2 mm). Sedangkan penentuan koordinat grid 8 angka dibagi menjadi sepuluh bagian (per 1mm).Beberapa manfaat penampang lintasan :1. Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan perjalanan2. Memudahkan kita untuk menggambarkan kondisi keterjalan dan kecuraman medan3. Dapat mengetahui titik-titik ketinggian dan jarak dari tanda medan tertentu.Untuk menyusun penampang lintasan biasanya menggunakan kertas milimeter block, guna menambah akurasi penerjemahan dari peta topografi ke penampang.Langkah-langkah membuat penampang lintasan:1.Siapkan peta yang sudah diplot, kertas milimeter blok, pensil mekanik/pensil biasa yang runcing, penggaris dan penghapus2. Buatlah sumbu x, dan y. sumbu x mewakili jarak, dengan satuan rata-rata jarak dari lintasan yang anda buat. Misal meter atau kilometer. Sumbu y mewakili ketinggian, dengan satuan mdpl (meter diatas permukaan laut). Angkanya bisa dimulai dari titik terendah atau dibawahnya dan diakhiri titik tertinggi atau diatasnya.3. Tempatkan titik awal di sumbu x=0 dan sumbu y sesuai dengan ketinggian titik tersebut. Lalu peda perubahan kontur berikutnya, buatlah satu titik lagi, dengan jarak dan ketinggian sesuai dengan perubahan kontur pada jalur yang sudah anda buat. Demikian seterusnya hingga titik akhir.4. Perubahan satu kontur diwakili oleh satu titik. Titik-titik tersebut dihubungkan sat sama lainnya hingga membentuk penampang berupa garis menanjak, turun dan mendatar.5. Tambahkan keterangan pada tanda-tanda medan tertentu, misalkan nama-nama sungai, puncakan dan titik-titik aktivitas anda (biasanya berupa titik bivak dan titik istirahat), ataupun tanda medan lainnya. Tambahan informasi tentang vegetasi pada setiap lintasan, dan skala penampang akan lebih membantu pembaca dalam menggunakan penampang yang telah dibuat. Peta topografi adalah peta yang menggambrakan penyebaran, bentuk dan ukuran dari rona muka bumi.
Yang dimaksud dengan rona muka bumi ( earth feature ) adalah meliputi :1. Relief yaitu beda tinggi rendah dari suatu tempat ke tempat lainnya pada suatu daerah, dan juga curam landainya lereng lereng yang ada. Termasuk dalam pengertian ini adalah bentuk bentuk bukit, lembah, datar, tebing, gunung, pegunumgan dan lainnya.2. Drainage yaitu pola pola pengaliran termasuk semua jalan jalan airt berupa sungai, danau, rawa-rawa, laut dan sebagainya.3. Culture yaitu semua bentuk bentuk hasil karya manusia seperti kota, desa, jalan raya, jalan kereta api, jalan setapak, batas administrasi daerah, dan lainnya.Untuk menggambarkan relief pata topografi dapat di pakai beberapa cara yaitu :1. Garis garis kontur yaitu dengan cara menghubungkan titik titik yang mempunyai harga ketinggian yang sama.2. Garis garis hachures yaitu dengan cara menghubungkan titik titik yang tinggi ke titik yang lebih rendah disekitarnya, dan ditarik searah dengan lereng. Makin curam lerengnya makin rapat garis garis yang ditarik.3. Pewarnaan yaitu dengan cara mewarnai dengan warna tertentu pada kisaran harga ketinggian tertentu.4. Pembayangan yaitu dengan cara membuat bayangan dari tempat tempat yang lebih tinggi. 2.4 Litologi Batuan
Gambar 2.6 Litologi batuanLitologi adalah sifat atau ciri dari batauan, terdiri dari struktur, warna, komposisi mineral, ukuran butir dan tata letak bahan-bahan pembentuknya. Litologi merupakan dasar penentuan hubungan atau korelasi lapisan-lapisan pada tambang batubara.2.4.1 Kesamaan Litologi dan Posisi StratigrafiPelacakan lateral secara langsung dari unit startigrafi dapat menjadi tidak berhasil diselesaikan dalam sebuah area yang sangat besar dikarenakan oleh ketidak menerusan singkapan. Geologist bekerja pada suatu area harus mempercayai korelasi unit lithostratigrafi dengan metode yang meliputimatchinglapisan dari suatu area ke lainya dengan dasar kesamaan lithologi dan posisi stratigrafi (Boggs, 1987).Persamaan litologi dapat tidak dipungkiri atas dasar suatu macam properties batuan. Meliputigross lithology(batupasir,serpih, atau batugamping, sebagi contoh), warna, kelompok mineral berat atau kelompok mineral khusus, struktur sedimen utama seperti perlapisan dan laminasi silang-siur, dan ketebalan rata-rata, dan karakteristik pelapukan. Lebih banyak macam properties yang dapat dipakai untuk menetapakan sebuah kesuaian antar strata maka semakin kuat kemungkinan menuju sebuah kesesuaian yang benar (Boggs, 1987).Penyesuaian lapisan dengan dasar lithologi merupakan tidak sebuah garansi atas kebenaran dari korelasi. Lapisan dengan karakteristik litologi yang sangat sama dapat terbentuk dalam lingkungan pengendapan yang sama dengan luas dipisahkan dalam waktu (time) atau tempat (space)(Boggs, 1987). Selain atas dasar kesamaan litologi, Individual formasi dapat dikorelasikan juga oleh posisi dalam sikuennya(Boggs, 1987).2.4.2 LitostratigrafiLitostratigrafi berhubungan dengan studi dan susunan lapisan berdasarkan karakteristiklitologi. Terminologi litologi digunakan oleh banyak geologist dengan dua macam cara, yakni :a. Litologi, merupakan pembelajaran dan deskripsi dari karakteristik fisik dari batuan khususnya pada batuan sampel dan di singkapan (Bates and Jackson, 1980).b. Litologi, merupakan karakteristik fisik, seperti tipe batuan, warna, komposisi mineral, dan ukuran butir.Berdasarkan hal tersebut kita dapat mendefinisikan satuan litologi sebagai satuan batuan yang didasarkan dengan karakteristik fisik sedangkan litostratigrafi berkaitan dengan studi mengenai hubungan stratigrafi antara lapisan yang dapat didefinisikan berdasarkan litologi.Satuan Litostratigrafi dapat terdiri dari batuan sedimen, metasedimen, batuan asal gunungapi (pre-resen) dan batuan hasil proses tertentu serta kombinasi daripadanya. Dalam hal pencampuran asal jenis batuan oleh suatu proses tertentu yang sulit untuk dipisahkan maka pemakaian kata Komplek dapat dipakai sebagai padanan dari tingkatan satuannya (misalnya Komplek Lukulo). Satuan Litostratigrafi pada umumnya sesuai dengan Hukum Superposisi, dengan demikian maka batuan beku, metamorfosa yang tidak menunjukkan sifat perlapisan dikelompokan ke dalam Satuan Litodemik. Sebagaimana halnya mineral, maka fosil dalam satuan batuan diperlakukan sebagai komponen batuan.Satuan Litostratigrafi Resmi ialah satuan satuan yang memenuhi persyaratan Sandi, sedangkan Satuan Litostratigrafi Tak Resmi ialah satuan yang tidak seluruhnya memenuhi persyaratan Sandi.Satuan tak resmi sedapat-dapatnya harus bersendi kepada ciri litologi;Bila ciri litologi tak dipergunakan, maka ciri-ciri yang didapat dengan cara mekanik, geofisika, geokimia atau penelitian lainnya, dapat pula dipakai sebagai sendi satuan tak resmi.
2.4.3 Tipe Satuan LitostratigrafiSatuan litostratigrafi merupakan tubuh batuan sedimen, beku, metasedimen atau metammorf yang dibedakan berdasarkan karakteristik litologi. Satuan litostratigrafi ini dapat dikenal berdasarkan karakteristik batuan yang dapat diteliti. Batas antar setiap satuan yang berbeda dapat diidentifikasi secara jelas dengan adanyakontakatau dapat dideskripsikan secara arbitrer karena bersifat gradasional.Pembedaan satuan stratigrafi ini didasarkan oleh stratotipe (tipe satuan yang ditentukan), dapat terdiri dari batuan yang ada, lokasi penemuan singkapan, penggalian, daerah tambang, yang mana semuanya mengacu pada kriteria batuan. Pada saat dilapangan, satuan stratigrafi yang terdiri dari hanya satu litologi saja jarang ditemukan. Umumnya satuan-satuan tersebut terdiri dari beberapa litologi yang saling berhubungan dan berbatasan. Hal yang penting adalah membedakan dan memahami kontak antar litologi tersebut secara vertikal dan lateral. Satuan litostratigrafi yang paling mendasar diantaranya :a. Formasi,merupakan suatu stratigrafi yang secara litologi dapat dibedakan dengan jelas dan dengan skala yang cukup luas cakupannya untuk dipetakan dipermukaan atau ditelusuri dibawah permukaan. Formasi dapat terdiri dari satu litologi atau beberapa litologi yang berbeda.b. Anggota,merupan bagian dari formasi (formasi dapat terbagi menjadi beberapa satuan stratigrafi yang lebih kecil yang disebut anggota).c. Perlapisan,merupakan bagian dari anggota (anggota dapat terbagi menjadi beberapa satuan stratigrafi yang lebih kecil yang disebut perlapisan).d. Kelompok/Grup,kombinasi dari beberapa formasi.e. Supergrup,kombinasi dari beberapa kelompok.Pengelompokan satuan stratigrafi menjadi satuan litostratigrafi yang lebih spesifik cakupannya dapat berguna untuk menelusiri dan mengkorelasikan lapisan baik pada singkapan dan dibawah permukaan.2.4.4 Batas dan Penyebaran LitostratigrafiBatas satuan litostratigrafi ialah sentuhan antara dua satuan yang berlainan ciri litologi, yang dijadikan dasar pembeda kedua satuan tersebut. Batas satuan ditempatkan pada bidang yang nyata, batasnya merupakan bidang yang diperkirakan kedudukannya (batas arbitrer).Satuan-satuan yang berangsur berubah atau menjari-jemari, peralihannya dapat dipisahkan sebagai satuan teresendiri apabila memenuhi persyaratan Sandi. Penyebaran suatu satuan litostratigrafi semata-mata ditentukan oleh kelanjutan ciri-ciri litologi yang menjadi ciri penentunya. Dari segi praktis, penyebaran suatu satuan litostratigrafi dibatasi oleh batas cekungan pengendapan atau aspek geologi lain. Batas-batas daerah hukum (geografi) tidak boleh dipergunakan sebagai alasan berakhirnya penyebaran lateral (pelamparan) suatu satuan. Batas satuan litostratigrafi tidak perlu berimpit dengan batas satuan stratigrafi lainnya (misalnya batas satuan waktu).
Gambar 2.7 Litologi-Litologi Batuan 2.5 Korelasi StratigrafiKorelasi adalah sebuah bagian fundamental dari stratigrafi, dan lebih lagi merupakan usaha dari stratigraphersdalam membuat unit stratigrafi yang formal yang mengarah pada penemuan praktis dan metode yang dapat dipercaya untuk korelasi unit ini dari suatu area dengan lainnya (Boggs, 1987).Dalam korelasi stratigrafi, pemahaman kita tentang korelasi sangat dipengaruhi oleh prinsip dasar, konsep baru dan peralatan analisa (analytical tools) sehingga bisa dihasilkan metode baru dalam korelasi.2.5.1 Definisi dan Prinsip KorelasiKorelasi ialah penghubungan titik-titik kesamaan waktu atau penghubungan satuan-satuan stratigrafi dengan mempertimbangkan kesamaan waktu (Sandi Startigrafi Indonesia, 1996). Menurut North American Stratigrafi Code (1983) ada tiga macam prinsip dari korelasi:1.Lithokorelasi, yang menghubungkan unit yang sama lithologi dan posisi stratigrafinya.2.Biokorelasi, yang secara cepat menyamakan fosil dan posisi biostratigrafinya.3.Kronokorelasi, yang secara cepat menyesuaikan umur dan posisi kronostratigrafi.Korelasi dapat dipandang sebagai suatu yang langsung (direct) (formal) ataupun tidak langsung (indirect) (informal) (B.R.Shaw,1982). Korelasi langsungadalah korelasi yang tidak dapat dipungkiri secara fisik dan tegas. Pelacakan secara fisik dari kemenerusan unit stratigrafi adalah hanya metode yang tepat untuk menunjukkan persesuaian dari sebuah unit dalam suatu lokal dengan unit itu di lokal lain. Korelasi tidak langsung dapat menjadi tidak dipungkiri oleh metode numerik seperti contoh pembandingan secara visual dari instrumen well logs, rekaman pembalikan polaritas,atau kumpulan fosil; meskipun demikian, seperti pembandingan mempunyai perbedaan derajat reabilitas dan tidak pernah secara keseluruhan tegas (tidak meragukan).Tabel 1 Hubungan dari Korelasi Langsung, Korelasi Tidak Langsung dan MatchingCorrelationFormalPhysical tracing of stratigraphic unit
Indirect
ArbitarySystematical
Visual comparisonsMonotheticPolythetic
Numeric EquivalenceStatistical Equivalence
MatchingComparisons of nonstrtigraphic units
Lithokorelasi merupakan metode yang digunakan untuk korelasi strata (lapisan) dengan dasar litologi.2.5.2 Pelacakan Kemenerusan Lateral dari Unit LitostratigrafiPelacakan kemenerusan secara langsung dari sebuah unit lithostratografi dari suatu local ke local lain adalah satunya metode korelasi yang dapat menetapkan kesamaan dari sebuah unit tanpa keraguan. Metode korelasi ini dapat digunakan hanya jika lapisan secara menerus atau mendekati menerus tersingkap. Jika singkapan dari lapisan tersela oleh daerah yang luas yang tertutup tanah dan vegetasi lebat, atau lapisan terhenti oleh erosi, atau dipotong lembah yang besar, atau tersesarkan, penelusuran secara fisik pada lapisan menjadi tidak mungkin. Dalam keadaan itu, teknik korelasi lainnya (tidak langsung) harus digunakan (Boggs, 1987).2.5.3 Kesamaan Litologi dan Posisi StratigrafiPelacakan lateral secara langsung dari unit startigrafi dapat menjadi tidak berhasil diselesaikan dalam sebuah area yang sangat besar dikarenakan oleh ketidak menerusan singkapan. Geologist bekerja pada suatu area harus mempercayai korelasi unit lithostratigrafi dengan metode yang meliputimatchinglapisan dari suatu area ke lainya dengan dasar kesamaan lithologi dan posisi stratigrafi (Boggs, 1987).Persamaan litologi dapat tidak dipungkiri atas dasar suatu macam properties batuan. Meliputigross lithology(batupasir,serpih, atau batugamping, sebagi contoh), warna, kelompok mineral berat atau kelompok mineral khusus, struktur sedimen utama seperti perlapisan dan laminasi silang-siur, dan ketebalan rata-rata, dan karakteristik pelapukan. Lebih banyak macam properties yang dapat dipakai untuk menetapakan sebuah kesuaian antar strata maka semakin kuat kemungkinan menuju sebuah kesesuaian yang benar (Boggs, 1987).Penyesuaian lapisan dengan dasar lithologi merupakan tidak sebuah garansi atas kebenaran dari korelasi. Lapisan dengan karakteristik litologi yang sangat sama dapat terbentuk dalam lingkungan pengendapan yang sama dengan luas dipisahkan dalam waktu (time) atau tempat (space)(Boggs, 1987).Selain atas dasar kesamaan litologi, Individual formasi dapat dikorelasikan juga oleh posisi dalam sikuennya(Boggs, 1987).2.5.4 Korelasi Dengan Instrumen Well LogsLog adalah suatu terminologi yang secara original mengacu pada hubungan nilai dengan kedalaman, yang diambil dari pengamatan kembali(mudlog). Sekarang itu diambil sebagai suatu pernyataan untuk semua pengukuran kedalam lubang sumur (Mastoadji, 2007).Secara prinsip pengunaan dari well logs adalah untuk:1. Penentuan lithologi2. Korelasi stratigrafi3. Evaluasi fluida dalam formasi4. Penentuan porositas5. Korelasi dengan data seismik6. Lokasi dari faults and fractures7. Penentuan dip dari strataSyarat untuk dapat dilakukannya korelasi well logs antara lain adalah 1. Deepest2. Thickest3. Sedikit gangguan struktur (unfaulted)4. Minimal ada 2 data well log pada daerah pengamatanPada sikeun sand-shale yang tebal, itu mungkin menjadi petunjuk kecil dari bentuk kurva untuk zona batuan untuk korelasi zona.Regional dip superimposedpada cross section sumur akan membantu. Unit pasir yang individual mungkin akan tidak menerus sepanjang lintasan, tetapi garis korelasi memberikan petunjuk tentangpossible timesikuen stratigrafi (Crain, 2008).
Gambar 2.8 Korelasi dengan instrumen Well LogsSequence Boundary(SB) merupakan batas atas dan bawah satuan sikuen stratigrafi adalah bidang ketidak selarasan atau bidang-bidang keselarasan padanannya (Sandi Stratigrafi Indonesia, 1996). Maximum flooding surfaceteridentifikasi oleh adanyamaximum landward onlapdari lapiasan marine pada batas basin dan mencerminkan kenaikan maksimum secara relatif darisea level (Armentout, 1991).
Gambar 2.9 Kandidat Sequence Boundary (SB) dan Maximum Flooding Surface (MSF) (Possamentier & Allen 1999)Untuk sikeun stratigrafi, biasanya dipakai Sequence Boundary (SB) dan Maximum Flooding Surface (MSF) untuk korelasi. Hal ini dikarenakan pelamparan SB dan MSF yang luas.Sequence Boundary (SB) danMaximum Flooding Surface(MFS) ini menandakan suatu proses perubahan muka air laut yang terjadi secara global. SehinggaSequence Boundary(SB) danMaximum Flooding Surface (MFS) ini sering digunakan untuk korelasi antar sumur. Dari data Well logs, adanyaSequence Boundary(SB) biasanya ditandai dengan adanya perubahan secara tiba-tiba dari Coarsening Upward menjadi Fineing Upward atau sebalikknya. SedangkanMaximum Flooding Surface(MFS) dari data log ditunjukkan dari adanya akumulasi shale yang banyak, dan MSF merupakan amplitude dari log yang daerah shale.
Gambar 2.10 Stratigraphic correlation of CSDP well Yaxcopoil-1 and PEMEX wells of the northern Yucatan Peninsula. Mesozoic are based on lithology, correlative fossil zones, and electric-log characteristics. (modified from Ward et al. 1995).
BAB IIIHASIL DAN PEMBAHASAN3.1 Hasil (Terlampir)
3.2. PembahasanTerdapat Peta Lokasi Bore Hole yang mempunyai empat titik (4) lubang Bor dengan kode tiap lubang bor adalah BH-01 (Bore Hole 01), BH-02 (Bore Hole 02), BH-03 (Bore Hole 03) dan BH-04 (Bore Hole 04).Pada Masing-masing titik bor memiliki kedalaman BH-01 25 m; BH-02 15 m ; BH-03 17 m ; BH-04 30 m.Pada bore hole BH-01 terdapat susunan dan struktur batuan seperti di bawah:KEDALAMAN (M)LITOLOGI
0 - 0.5SOIL
0.5 - 5CLAY
5 - 6.5COAL
6.5 - 6.7COALY MUDSTONE
6.7 - 7COAL
7 - 7.5CLAY
7.5 - 14SAND
14 - 16MUDSTONE
16 - 19COAL
19 - 21MUDSTONE
21 - 25SAND
Pada bore hole BH-02 terdapat susunan dan struktur batuan seperti di bawah:KEDALAMAN (M)LITOLOGI
0 - 0.7SOIL
0.7 - 4CLAY
4 - 5.3COAL
5.3 - 6COALY MUDSTONE
6 - 6.5COAL
6.5 - 9CLAY
9 - 15.SAND
Pada bore hole BH-03 terdapat susunan dan struktur batuan seperti di bawah:KEDALAMAN (M)LITOLOGI
0 - 0.15SOIL
0.15 - 3CLAY
3 - 4.5COAL
4.5 - 5COALY MUDSTONE
5 - 7.COAL
7 - 8.CLAY
8 - 17.SAND
Pada bore hole BH-04 terdapat susunan dan struktur batuan seperti di bawah:KEDALAMAN (M)LITOLOGI
0 - 0.1SOIL
0.1 - 3CLAY
3 - 4.5COAL
4.5 - 5COALY MUDSTONE
5 - 5.3COAL
5.3 - 6CLAY
6 - 15.SAND
15 - 15.50MUDSTONE
15.50 - 18COAL
18 - 24MUDSTONE
24 - 30SAND
Lampiran 1Dari data bore hole dapat dibuat dan di jelaskan seperti pada lampiran 1. Pada lampiran 1 terdapat kedalaman dan litologi dari setiap log bor. Dimana log bor tersebut di gambar dengan skala kedalaman 1 : 100. Jadi 1 cm = 1 m.Pada log bor bagian atas digambar meruncing karena data yang di setiap bore hole adalah data dari lapangan yang ada pada bor, sehingga kita tidak tau pasti diatas itu ada jenis lapisan apa. Dan pada bagian bawah sedikit melengkung karena kita tidak tahu apa jenis batuan yang ada berikutnya setelah gambar dari data bore hole. Dibuatnya lampiran 1 itu dikarenakan pada gambar penampang dan log bor tidak bias dibuat dengan jelas litologinya sehingga kami membuat perbesaran untuk memudahkan pembaca apa saja litologi dari lapisan batuan tersebut.
Lampiran 2Pada lampiran 2 ini adalah gambar dari penampang dan logbor, dimana pada lampiran 2 ini hanya di tunjukkan posisi setiap bore hole. Sebenarnya posisi logbor yang ada pada lampiran dua tidak sejajar seperti gambar. Tetapi karena logbornya dihubungkan dengan penampang yang ada pada peta makakelihatan seperti sejajar. Namun sebenarnya tiidak sejajar. Pada lampiran ini hanya menerangkan penampang dan litologi logbor.Skala yang digunakan pada lampiran 2 ini berbeda-beda seperti yang di jelaskan di lampiran itu dikarenakan skala peta terlalu kecil untuk logbor sehingga akan sulit untuk menggambarnya, sehingga dilakuukan pengubahan sekala agar sesuai dengan luasan tempat gambar. Skala yang digunakan pada lampiran adalah:1. Vertical adalah skala 1: 2000,2. Horizontal adalah skala 1:1000, 3. Logbor adalah skala 1:200Sehingga untuk vertical 1 cm di gambar sama dengan 20 meter dilapangan dan untuk horizontal menggunakan skala pada peta sehingga 1 cm di peta sama dengan 10 meter di lapangan. Pada logbor 1 cm digambar samadengan 2 m dilapangan.
Lampiran 3Pada lampiran 3 itu terdapat korelasi seluruh logbor dalam penampang. Pada lampiran ini dapat kita lihat korelasi dari semua logbor yang ada pada peta dan dapat di lihat dan dapat dibayangkan tebal dari setiap lapisan batuan serta tebal dan kemiringan dari lapisan batubara dan dapat juga dipastikan arah persebaran dari sim atau cadangan batubaranya. Skala yang digunakan pada lampiran ini sama dengan skala pada lampiran 2.
BAB IVPENUTUP4.1 KesimpulanPenggambaran profil melintang bertujuan untuk memperlihatkan bentuk topografi dalam tiap segmen. Segmen disini diartikan sebagai titik ketinggian dan jarak. Pada ketinggian berapa keadaan topografi berlereng landai, terjal sampai sangat terjal dan beberapa derajat kemiringan lereng tiap segmen adalah salah satu contoh yang bisa diketahui dari profil melintang. Pemboran adalah salah satu kegiatan penting dalam sebuah industri pertambangan. Kegiatan pemboran biasanya dilakukan sebelum diadakannya penambangan. Dalam eksplorasi, pemboran dilakukan untuk mendapatkan data log bor.. Korelasi ialah penghubungan antara titik-titik kesamaan waktu atau penghubungan antara satuan-satuan stratigrafi dengan mempertimbangkan kesamaan waktu.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2009. Batubara. URL : www.wikipedia.org [Online : 15 Oktober 2009]Anonim. 2006. Litbang Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Batubara URL : www.ilmubatubara.wordpress.com [Online : 15 Oktober 2009]Erwan. Kelas dan Jenis Batubara. URL : www.tamangeologi.blogspot.com [Online : 15 Oktober 2009]Sukandarrumidi. 2008. Batubara dan Gambut. Yogyakarta : UGM Presshttps://www.academia.edu/7302602/Laporan_Proposal_Eksplorasi_Batubara_di_Cekungan_Kutai_Balikpapan_Kalimantan_Timur_-_Johan_Edwarthttp://suarageologi.blogspot.com/2014/01/geologi-pulau-kalimantan.html
http://aaichsancr.blogspot.com/2012/01/cekungan-dan-formasi-di-kalimantan.html
46 | PagePENAMPANG DAN LOGBOR