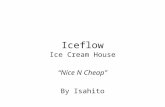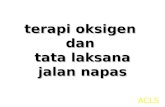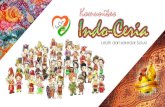BPFR NEW
-
Upload
lia-kusuma -
Category
Documents
-
view
305 -
download
0
Transcript of BPFR NEW
BAB I PENDAHULUAN
Usaha di bidang peternakan selalu melibatkan 3 hal yaitu breeding (pembiakan), feeding (pemberian pakan) dan management (tata laksana pemberian pakan). Tata laksana pemberian pakan mencakup jenis, jumlah, Bahan dan cara pemberian bahan pakan yang akan dikonsumsi oleh ternak. Bahan pakan memiliki Bahan zat gizi tertentu untuk memenuhi kebutuhan ternak guna menampilkan hasil produksi daging, telu atau susu yang optimal. Para ahli makanan ternak telah mencoba untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui jenis dan Bahan makanan ternak sehingga dapat digunakan dalam penyusunan ransum dengan cara sederhana. Salah satu caranya melalui analisis proksimat yang dikembangkan oleh Weende Experiment Station (Jerman) yang membagi Bahan bahan pakan ke dalam 6 fraksi yaitu, air, ekstrak eter atau lemak kasar, serat kasar, protein kasar, bahan ekstrak tanpa nitrogen dan abu. Praktikum Bahan Pakan dan Formulasi Ransum menggunakan bahan pakan tepung ikan untuk dianalisis sehingga dapat diketahui Bahannya berdasarkan analisis proksimat. Tujuan praktikum ini adalah mengetahui cara menganalisis bahan pakan dengan analisis proksimat Weende dan mengetahui Bahan bahan pakan berdasarkan analisis tersebut. Manfaat praktikum ini adalah praktikan
mengetahui lebih jelas metode analisis proksimat Weende sebagai pengetahuan untuk diterapkan saat kita membutuhkannya.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Analisis Proksimat Analisis proksimat merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui kadar nutrisi bahan pakan dengan prinsip mendekati nilai yang sebenarnya. Fraksi bahan pakan dalam analisis proksimat adalah air, abu, protein kasar, lemak kasar, serat kasar dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (Tillman et al., 1998). Kelemahan analisis proksimat diantaranya yaitu terdapat VFA yang ikut menguap dalam pengovenan dengan suhu 105-1100 C sehingga terhitung dalam kadar air, pada proses tanur terdapat pula bahan organik yang turut terlarut dan menjadi abu, vitamin larut dalam analisis lemak kasar, nitrogen bukan protein ikut tertangkap dan terhitung dalam kadar protein kasar serta tidak semua serat kasar terlarut pada analisis serat kasar. Oleh karena kelemahan tersebut, maka analisis ini disebut sebagai analisis proksimat (Kartadisastra, 1997). 2.1.1. Air Air mengandung dua atom hydrogen dan satu atom oksigen serta merupakan bagian terbanyak serta terpenting dari jaringan hewan maupun tumbuhtumbuhan (Anggorodi, 1997). Air merupakan unsur terpenting yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, lebih dari 50% bobot badan ternak adalah air yang mengisi sel-sel tubuh dengan konsentrasi antara 70-90%, oleh pembatasan konsumsi air akan mempengaruhi ketahanan karena itu hidupnya
(Kartadisastra, 1997), misalnya pada musim penghujan kadar air rumput meningkat,
sebaliknya dimusim kemarau kadar air susut (Sutardi, 1980). Menurut Tillman et al. (1998), kadar air suatu bahan pakan dapat diketahui bila bahan pakan tersebut dipanaskan atau dikeringkan pada suhu 105110 oC. Bungkil kedelai mempunyai kadar air sebesar 11,6% dengan kadar bahan kering 88,4 % (Lubis, 1992). Analisis proksimat dalam menentuan kadar air pakan dilakukan dengan pemanasan 105oC secara terus-menerus sampai beratnya konstan. Produk biologi bila dipanaskan dengan temperatur 70o C akan kehilangan zat-zat volatil (zat-zat yang mudah menguap) sehingga untuk penentuan kadar yang tepat dapat dilakukan melalui pemanasan dengan temperatur yang lebih rendah dan dengan menggunakan desikator dapat divakum, tetapi karena alat ini sangat terbatas kapasitasnya sampel yang dapat dianalisis juga terbatas (Tillman et al.,
1998). Ukuran berat air adalah berat sebelum dipanaskan dikurangi dengan ukuran berat sesudah dipanaskan. Kadar air dihitung berdasarkan kehilangan bobot sampel setelah dikeringkan dalam oven sampai bobotnya konstan (Anggorodi, 1997). Kadar bahan kering pada suatu bahan dihitung sebagai selisih antar berat segar dengan kadar air (Sutardi, 1980). Kelemahan dalam analisis kadar air yaitu terdapat vitamin-vitamin yang ikut menguap karena terlarut dalam air seperti vitamin B dan C (Kartadisastra, 1997).
2.1.2. Abu
Kadar abu dalam bahan pakan merupakan sisa pembakaran dalam tanur pada suhu 400-600oC (Sutardi, 1980). Bahan pakan yang dipanaskan pada temperatur 600oC selama 4-6 jam akan menghasilkan abu dan sejumlah zat anorganik yang terkandung di dalam bahan pakan (Kartadisastra, 1997). Semua bahan organik yaitu karbohidrat, lemak, dan protein terbakar habis dan sisanya yaitu abu yang merupakan bahan anorganik. Abu hasil pembakaran dapat digunakan untuk determinasi persentase zat-zat tertentu yang terdapat dalam bahan pakan seperti mineral makro maupun mikro (Anggorodi, 1997). Kadar abu dalam bahan kering adalah sebesar 5-7 % (Rasyaf, 1990). Analisis kadar abu untuk mengetahui kadar abu bahan dengan membakar bahan baku pakan, biasanya hanya zat organik, selanjutnya ditimbang dan sisanya disebut abu. Kadar abu dalam Bahan bahan unggas umumnya hanya dicantumkan kadar calsium (Ca) dan Fosfor (P) (Murtidjo, 1987). Komponen abu dalam analisis proksimat tidak memberikan nilai makanan yang penting, namun jumlahnya dalam bahan pakan hanya penting untuk menentukan perhitungan BETN. Bahan pakan yang berasal dari hewan, kadar abu berguna sebagai indek untuk kadar kalsium dan fosfor, pada bahan pakan yang berasal dari tumbuhan terutama biji yang mengandung minyak, mempunyai kadar kalsium lebih banyak bila dibandingkan dengan biji lain (Tillman et al., 1998). Pengabuan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara basah atau wet ashing dengan menggunakan oksidator kuat dan cara kering atau dry ashing den gan tanur pada suhu memijarkan sampel atau bahan pakan dalam 400-600oC (McDonald et al, 1978).
2.1.3. Protein Kasar Protein adalah zat organik yang mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur dan fosfor. Protein adalah senyawa organik kompleks yang mempunyai berat molekul tinggi, mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen, mengandung pula nitrogen, serta sulfur dan fosfor (Anggorodi, 1997). Protein kasar merupakan kumpulan lebih dari 20 asam amino dan tiap-tiap asam amino mempunyai fungsi khusus di dalam metabolisme (Anggorodi, 1997). Kadar nitrogen dari bahan pakan ditentukan dengan cara Kjeldahl, yang hasilnya dikalikan dengan faktor koreksi 6,25, karena nitrogen mewakili sekitar 16% dari protein (Tillman et al, 1998). Kelemahan kjeldahl dalam analisis protein pakan adalah penetapan kadar protein tersebut berdasarkan jumlah N yang terkandung dalam bahan pakan, sehingga zat-zat protein bukan nitrogen ikut teranalisis (Rasyaf, 1990). Protein bungkil kedelai dalam BK adalah sebesar 20-26 % (Rasyaf, 1990). 2.1.4. Lemak Lemak terbentuk dari unsur-unsur C, H, dan O (Lubis, 1992). Lemak adalah lipida sederhana yaitu ester dari tiga asam-asam lemak dan gliserol
(Tillman et al, 1998). Lemak hasil analisis proksimat ditetapkan sebagai ekstrak eter (Anggorodi, 1997). Termasuk lipida adalah semua substansi yang dapat diekstraksi dari bahan-bahan biologik dengan pelarut lemak eter, kloroform, benzena karbon tetrakloride, aseton dan lain-lain (Tillman et al,1998). Bahan pakan diekstraksi dengan eter akan terurai menjadi lemak dan
karbohidrat, lemak yang diperoleh adalah lemak yang terkandung dalam bahan pakan (Kartadisastra, 1997). Lemak kasar dalam bahan pakan ternak yang berasal dari hewan biasanya terdiri dari gliserol dan tiga asam lemak tetapi dalam pakan ternak yang berasal dari tanaman, sterol, lilin, dan berbagai produk seperti vitamin A, vitamin D dan karotin seringkali menyusun sampai lebih dari 50% lemak makanan (Tillman et a., 1998). Hasil analisis lemak disebut lemak kasar karena dalam ekstraksi yang terekstraksi tidak hanya lemak, melainkan juga bahan-bahan yang larut dalam eter yaitu steroid, pigmen tanaman, karotinoid, wax dan vitamin larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K semua hal tersebut masih terhitung sebagai lemak (Sutardi, 1980). Kadar lemak bungkil kedelai sebesar 1,3 % (Hartadi, 1997). Hasil analisis menunjukkan nilai yang lebih besar, disebabkan oleh penyimpanan sampel yang menyebabkan kerusakan lemak (Tillman et al., 1998). Penggunaan lemak dalam ransum berperan untuk menaikkan nilai energi sehingga akan menghasilkan daya produksi lebih tinggi dan kualitas lebih baik (Anggorodi, 1997). Penambahan lemak pada ransum akan membuat warna ransum lebih menarik, menambah cita rasa, serta mengurangi hilangnya zat pakan akibat debu (Anggorodi, 1997). Bahan pakan diekstraksi dengan eter akan terurai menjadi lemak dan karbohidrat, yang diperoleh adalah lemak yang terkandung dalam bahan ( Kartadisastra, 1997) lemak pakan
2.1.5. Serat Kasar
Penetapan karbohidrat dalam analisis bahan makanan dibagi menjadi golongan yaitu serat kasar dan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen
dua
(BETN)
(Tillman et al, 1991). Semua zat-zat organik yang tidak dapat larut dalam H2SO4 0,3 N dan dalam NaOH 1,5 N yang berturut-turut dimasak selama 30 menit disebut serat kasar, yang merupakan selulosa, lignin, dan sebagian dari (Anggorodi, 1997). Serat kasar mengandung bahan-bahan yang terbentuk dari dinding-dinding sel tumbuhan, yang termasuk golongan ini adalah selulosa, pentosan, lignin, dan kitin. Lignin dan kitin sama sekali tidak dapat dicerna, sedangkan selulosa pentosan dapat dicerna dengan bantuan mikroorganisme rumen ruminansia (Lubis, 1992). Kadar serat kasar tanaman yang makin pencernaannya makin lama dan nilai energi produktifnya dan pada tinggi, rendah pentosan-pentosan
(Tillman et al, 1991). Kadar serat kasar bungkil kedelai dalam BK sebesar 5,1% (Hartadi, 1997). 2.1.6. Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) BETN suatu senyawa terdiri dari zat-zat monosakarida, disakarida, dan polisakarida yang mudah larut dalam larutan asam dan basa serta serat kasar mempunyai daya cerna yang tinggi (Anggorodi, 1997). Zat tersebut mempunyai kandungan energi yang tinggi sehingga digolongkan dalam makanan sumber energi yang tidak berfungsi spesifik. Kadar BETN adalah 100% dikurangi kadar abu, protein, lemak kasar dan serat kasar, maka nilainya tidak selalu tepat serta dapat dipengaruhi oleh kesalahan analisa dari zat-zat lain (Tillman et al, 1998). Biji-bijian
seperti jagung, padi, gandum mengandung banyak BETN rata-rata lebih dari 50% (Lubis, 1992). Kadar BETN bungkil kedelai adalah 35% (Hartadi,1997). Kesalahan pokok bagan analisa proksimat adalah mengingat kenyataan bahwa ekstraksi alkali lemak yang dipakai pada penentuan serat kasar memisahkan sebagian lignin dari beberapa rumput dan karenanya mengurangi kadar serat kasar rumput, seakan-akan nilai BETN naik. Namun kesalahan-kesalahan tersebut tidak mengkhawatirkan pada analisa yang telah sering dilakukan karena selulosa dan pati adalah komponen utama bahan makanan dan bagan tidak memisahkan bagian ini (Tillman et al, 1991). Kelemahan selain kehilangan beberapa komponen adalah lambat dan menjemukan (Church, 1991). Selanjutnya dijelaskan bahwa beberapa hemiselulosa akan dihancurkan oleh perlakuan kimiawi, protein berbentuk lignin dan zat kimia lainnya yang tidak terlarut akan terhitung sebagai serat kasar. Cara ini adalah penentuan yang tidak terlalu teliti dari prosedur analisis proksimat, namun masih dipakai secara umum untuk menilai bahan makanan (Srigandono, 1996). 2.2.Bungkil Kedelai Pakan adalah bahan yang dimakan dan dicerna oleh seekor hewan yang mampu menyajikan hara atau nutrien yang penting untuk perawatan tubuh, pertumbuhan, penggemukan, reproduksi (birahi, konsepsi, kebuntingan) serta laktasi (produksi susu) (Blakey dan Bade, 1994). Kedelai adalah tanaman yang kandungan proteinnya paling banyak, bungkil kedelai sangat baik untuk ternak, kandungan protein tetap tinggi dan harganya jauh lebih murah. Selain itu,
kandungan lemak jauh lebih rendah daripada kedelai (Lubis, 1992).
BAB III METODOLOGI Praktikum Bahan Pakan dan Formulasi Ransum dengan kegiatan analisis kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, kadar serat kasar, dilaksanakan pada tanggal 11-12 November 2010 pukul 07.00 21.30 WIB dan 07.00 22.30 WIB di Laboratrium Ilmu Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro Semarang.
Materi Materi yang digunakan dalam praktikum Bahan Pakan dan Formulasi Ransum adalah bungkil kedelai, selenium 0,3 gr, H3BO3 4%, katalisator (campuran selenium+natrium sulfat+cupri sulfat), HCl 0,1 N, aseton, aquades, NaOH 1,5 N, NaOH 45%, indikator (methyl merah + methyl biru), diethyl ether, H2SO4 0,3 N, H2SO4 pekat, dan air panas. Alat yang digunakan meliputi botol timbang, timbangan analitis, oven, eksikator, pinset, cawan porselen, tanur listrik, labu destruksi, labu erlenmeyer, gelas beker, lemari asam, alat destilasi, alat titrasi, labu penyaring abu, penyaring biasa, soxhlet, pendingin tegak, water bath, kertas lemak, kertas whatman, kertas minyak, corong buchner, pipet, dan gelas ukur.
Metode Kadar Air Metode yang digunakan dalam analisis kadar air adalah mencuci botol timbang kemudian mengeringkan dalam oven selama 1 jam pada suhu 105-110C kemudian mengambil dengan piset dan dinginkan dalam eksikator selama 15 menit dan kemudian menimbang serta catat beratnya. Timbang sempel 1 gram kemudian masukkan kedalam botol timbang dan mengeringkan dalam oven selama 4-6 jam pada suhu 105-110C. Langkah selanjutnya adalah memasukkannya dalam eksikator selama 15 menit, kemudian melakukan penimbangan. Pengeringan melakukan berulang kali sampai mencapai berat konstan atau beratnya tidak berubah lagi (maksimal 0,1 mg). Rumus perhitungan kadar air sampel adalah sebagai berikut: Kadar Air = Keteragan:x+ yz x100% y
x = berat botol timbang (gram) y = berat sampel (gram) z = berat botol timbang + sampel setelah dioven (gram)
3.1.1. Kadar Abu Metode yang digunakan dalam analisis kadar abu adalah mencuci dan mengeringkan cawan porselen dalam oven pada suhu 105C-110C selama 1jam. Kemudian mendinginkan cawan dalam eksikator selama 15 menit dan menimbang serta catat beratnya. Langkah selanjutnya adalah menimbang sampel 1 gram lalu
masukkan kedalam cawan porselen. Kemudian memijarkan sampel dalam tanur listrik pada suhu 400C-600C selama 4-6 jam, sampai menjadi abu putih semua. Langkah selanjutnya adalah mengangkat cawan porselen dari tanur listrik dan mendinginkan sebentar sampai suhu sekitar 200C. Mendinginkan sampel dalam eksikator selama 15 menit dan menimbang sampel, yang dicatat sebagai z gram. Rumus perhitungan untuk analisis kadar abu adalah: Kadar abu = Keterangan:zx x100% y
x y z
= berat cawan porselin setelah dioven = berat sampel = berat cawan porselin dan sampel setelah ditanur
3.1.2. Kadar Protein Kasar Metode yang digunakan dalam analisis kadar protein adalah menimbang sampel sebanyak x gram, kemudian memasukkan ke dalam labu destruksi yang ditambah selenium 1 gram ditambah H2SO4 pekat 20 ml. Memanaskan labu destruksi dan sampel ke dalam lemari asam. Pemanasan dihentikan sampai larutan menjadi berwarna hijau jernih. Memasukkan hasil destruksi kedalam labu destilasi kemudian ditambah 50 ml aquades dan NaOH 45% sebanyak 40 ml. Hasil ditampung dalam erlenmeyer yang berisi H3BO3 4% 20 ml dan menambahkan indikator MR + MB sebanyak 1 tetes. Menitrasi hasil sulingan dengan HCL 0,1 N sampai terjadi perubahan warna dari ungu menjadi hijau. Jumlah titran sebagai z gram. Membuat larutan blanko dengan memasukkan aquades 50 ml dan NaOH 45%
40 ml ke dalam labu destilasi. Hasilnya ditangkap dengan H3BO3 4% 20 ml yang ditambah dengan indikator MR + MB sebanyak 2 tetes. Rumus perhitungan untuk analisis kadar protein adalah: Kadar Protein: Keterangan: ( y z ) xNHCLx0.014 x6.25 x 100% x y = titran sampel Z = titran blanko X = berat sampel 0,014 = 1 ml larutan alkali~ larutan N yang mengandung 0,014 gram N 6,25 = protein mengandung 16 % N
3.1.3. Kadar Lemak Kasar Metode yang digunakan dalam analisis kadar lemak adalah mengoven kertas saring selama 1 jam pada suhu 1050-1100 C. Menimbang sampel misalkan x gram, kemudian membungkus sampel dengan kertas saring dan mengoven pada suhu 105-110C kemudian memasukkannnya ke dalam eksikator selama 15 menit, dan menimbangnya misalnya z gram. Selanjutnya melakukan proses ekstraksi dengan memasukkan sampel dan kertas saring ke dalam soxlet yang telah terpasang dalam water bath, lalu menuangkan diethyl ether ke dalam labu penyari dan selanjutnya memasang alat pendingin tegak yang dialiri air. Kemudian melakukan proses penyaringan sampai 10 kali sirkulasi. Kertas saring dan isi diangkat dari soxlet dan mengangin-anginkannya, setelah itu memasukan ke dalam oven selama 2 jam dan dieksikator selama 15 menit lalu menimbangnya sebagai y gram.
Rumus perhitungan untuk analisis kadar lemak adalah:
a b x 100% Kadar Lemak = a kertas saring
Keterangan: a = kertas saring + sampel setelah di oven sebelum diekstraksi b = kertas saring + sampel setelah diekstraksi setelah dioven
3.1.4. Kadar Serat Kasar Metode yang digunakan dalam analisis serat kasar adalah memasukkan beker glass yang telah dicuci dan kertas saring Whatman kedalam oven selama satu jam pada suhu 1050C-1100C dan mendinginkan dalam eksikator selama 15 menit. Menimbang sampel menggunakan kertas minyak seberat x gram dan memasukkan ke dalam beaker glass kemudian menambahkan 50 ml H2SO4 0,3 N dan memasaknya hingga mendidih selama 30 menit. Menambahkan 25 ml NaOH 1,5 N ke dalam beaker glass kemudian memasaknya hingga mendidih selama 30 menit. Menyaring cairan tersebut dengan kertas saring whatman yang telah dipasang pada corong Buchner (misal berat kertas saring a gram). Kemudian mencuci hasil saringan berturutturut dengan 50 ml air panas, 50 ml H2SO4 0,3 N, 50 ml air panas dan 25 ml aceton. Memasukkan kertas saring dan sampel ke dalam cawan porselin dan mengeringkannya dalam oven pada suhu 1050C-1100C selama 5 jam, kemudian mendinginkannya dalam eksikator selama 15 menit dan menimbangnya dengan berat misalnya y gram kemudian memasukkan ke dalam tanur pada suhu 4000C6000C selama 4-6 jam. Mengangkat cawan porselin dari tanur setelah mencapai suhu 2000C dan memasukkannya kedalam eksikator selama 15 menit serta menimbangnya dengan berat z gram.
Rumus perhitungan untuk analisis kadar serat kasar adalah: Kadar serat kasar = Keterangan: x y z ayza x100% x = berat sampel = berat sampel + kertas saring Whatman + cawan sebelum ditanur = berat sampel + cawan setelah ditanur = berat kertas saring Whattman
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Kadar Air Hasil analisis bungkil kedelai diperoleh kadar air sebesar 14,14 % dengan bahan kering 85,86 %. Hal ini tidak mendekati standar kadar air. Dijelaskan lebih lanjut oleh Lubis (1992) yang menyatakan bahwa bungkil kedelai
mempunyai kadar air sebesar 11,6% dengan kadar bahan kering 88,4 %. Menurut Tillman et al. (1998) kadar air suatu bahan pakan dapat diketahui bila bahan pakan tersebut dipanaskan atau dikeringkan pada suhu 105110 oC. Kita perlu mengetahui kadar air dari suatu bahan pakan yang akan digunakan, agar ransum yang disusun dapat memenuhi kebutuhan gizi ternak tersebut. Analisis proksimat dalam menentukan kadar air pakan dilakukan dengan pemanasan 1050C secara terus menerus sampai beratnya. Hasil yang diperoleh dalam analisis tersebut tidak mendekati standar disebabkan karena sampel dipanaskan pada suhu 105-1100 C sehingga tidak hanya air yang menguap namun, vitamin serta zat organik juga ikut menguap sehingga kadar air menjadi lebih tinggi. Dijelaskan lebih lanjut oleh Kartadisastra (1997) berpendapat bahwa kelemahan dalam analisis kadar air yaitu terdapat vitaminvitamin yang ikut menguap karena terlarut dalam air seperti vitamin B dan C.
4.2.
Kadar Abu
Hasil praktikum menunjukkan hasil analisis kadar abu bungkil kedelai sebesar 6,16 % dengan hasil konversi dalam bahan kering sebesar 7,18%. Hal ini mendekati dengan literatur Rasyaf (1990) yang menyatakan bahwa kadar abu dalam bahan kering adalah sebesar 5-7 %. Menurut Mc Donald (1978) proses pengabuan secara kering (dry ashing), yaitu dengan menggunakan tanur 400 oC yang menyebabkan berkurangnya mineral-mineral yang volatil pada temperatur tinggi sehingga memungkinkan adanya perbedaan pada hasil analisis dari ketentuan bahan bahan tersebut. Sesuai dengan pendapat Tillman et al., (1998) bahan pakan yang berasal dari hewan, kadar abu berguna sebagai indek untuk kadar kalsium dan fosfor, pada bahan pakan yang berasal dari tumbuhan terutama biji yang mengandung minyak, mempunyai kadar kalsium lebih banyak bila dibandingkan dengan biji lain. 4.3. Kadar Protein Hasil praktikum menunjukkan hasil analisis kadar protein bungkil kedelai adalah 38,48 % dan berdasarkan 100% bahan kering sebesar 44,82 %. Ini berarti kadar bahan kering tidak mendekati standar. Dijelaskan lebih lanjut oleh
Rasyaf (1990), yang menyatakan bahwa protein dalam BK sebesar 20-26 %. Hal itu disebabkan oleh pemanasan yang terlalu lama sehingga asam amino yang terkandung dalam BK akan rusak. Menurut Tillman et al., (1998), kadar nitrogen dari bahan pakan ditentukan dengan cara Kjeldahl, yang hasilnya dikalikan dengan faktor koreksi 6,25 karena nitrogen mewakili sekitar 16% dari protein. Rasyaf (1990) menjelaskan bahwa kelemahan Kjeldahl dalam analisis protein pakan adalah
penetapan kadar protein tersebut berdasarkan jumlah N yang terkandung dalam bahan pakan sehingga zat-zat protein bukan nitrogen ikut teranalisis.
4.4.
Kadar Lemak
Hasil analisis kadar lemak bungkil kedelai adalah 2,72 %. Hal ini mendekati standard kadar lemak pada bungkil kedelai. Dijelaskan lebih lanjut oleh Hartadi (1997) bahwa kadar lemak bungkil kedelai sebesar 1,3 %. Tillman et al., (1998)
menjelaskan bahwa hasil analisis menunjukkan nilai yang lebih besar, disebabkan oleh penyimpanan sampel yang menyebabkan kerusakan lemak. Penyebab lain yaitu karena terdapat wax, steroid, pigmen tanaman, karotiroid dan vitamin A, D, E, K yang ikut terlarut dalam ether saat dilakukan uji kadar lemak. Sutardi (1980) berpendapat bahwa kelemahan dari analisis proksimat pada lemak kasar adalah terdapat wax, steroid, pigmen tanaman, karotinoid dan vitamin A, D, E, K yang ikut larut dalam ether. Menurut Anggorodi (1997), penggunaan lemak dalam ransum berperan untuk menaikkan nilai energi sehingga akan menghasilkan daya produksi lebih tinggi dan kualitas lebih baik. Lebih lanjut dijelaskan Anggorodi (1997), penambahan lemak pada ransum akan membuat warna ransum lebih menarik, menambah cita rasa, serta mengurangi hilangnya zat pakan akibat debu. Menurut Kartadisastra (1997) bahan pakan diekstraksi dengan eter akan terurai menjadi lemak dan karbohidrat, lemak yang diperoleh adalah lemak yang terkandung dalam bahan pakan.
4.5.Kadar Serat Kasar
Hasil analisis kadar serat kasar dalam praktikum adalah 0,32 % dan setelah dikonversikan berdasarkan 100% bahan kering adalah 0,37 %. Hal ini tidak mendekati standard. Dijelaskan lebih lanjut oleh Hartadi (1997) bahwa kadar serat kasar bungkil kedelai dalam BK sebesar 5,1%. Hasil analisis yang lebih kecil dapat disebabkan oleh adanya bahan-bahan organik yang ikut menguap pada proses pemasakan dan ikut larut pada waktu pencucian sampel, dengan H2SO4 0,3 N dan NaOH 1,5 N.Tillman et al.,(1991), menjelaskan kadar serat kasar tanaman yang makin tinggi, pencernaannya makin lama dan nilai energi produktifnya rendah. Menurut Anggorodi (1997) semua zat-zat organik yang tidak dapat larut dalam H2SO4 0,3 N dan dalam NaOH 1,5 N yang berturut-turut dimasak selama 30 menit disebut serat kasar, yang merupakan selulosa, lignin, dan sebagian dari pentosanpentosan.
4.6.Kadar BETN Hasil analisis kadar BETN dalam praktikum adalah 44,91%. Hasil yang diperoleh tidak mendekati standard. Dijelaskan lebih lanjut oleh Hartadi (1997) menyatakan bahwa kadar BETN bungkil kedelai adalah 35%. Menurut Tillman et al, (1998) kadar BETN adalah 100% dikurangi kadar abu, protein, lemak kasar dan
serat kasar, maka nilainya tidak selalu tepat serta dapat dipengaruhi oleh kesalahan analisa dari zat-zat lain. Ditambahkan oleh Tillman et al, (1991), bahwa kesalahan pokok bagan analisa proksimat adalah mengingat kenyataan bahwa ekstraksi alkali lemak yang dipakai pada penentuan serat kasar memisahkan sebagian lignin dari beberapa rumput dan karenanya mengurangi kadar serat kasar rumput, seakan-akan nilai BETN naik. Namun kesalahan-kesalahan tersebut tidak mengkhawatirkan pada analisa yang telah sering dilakukan karena selulosa dan pati adalah komponen utama bahan makanan dan bagan tidak memisahkan bagian ini.
BAB V
KESIMPULANPraktikum analisis proksimat membagi Bahan zat pakan ke dalam fraksi kadar air, abu, protein kasar, lemak kasar, serat kasar dan BETN. Bahan pakan yang dianalisis adalah bungkil kedelai. data sebagai berikut: Hasil analisis tepung ikan diperoleh kadar air sebesar 4,2605% dengan bahan kering 95,795% dan setelah dikonversikan kedalam 100% BK diperoleh 4,4475%. Hasil praktikum
menunjukkan hasil analisis kadar abu tepung ikan sebesar 21,038% dengan hasil konversi dalam bahan kering sebesar 21,96%. Hasil praktikum menunjukkan hasil analisis kadar protein tepung ikan adalah 3,63% dan berdasarkan 100% bahan kering sebesar 3,5075%. Hasil analisis kadar serat kasar dalam praktikum adalah 3,05% dan berdasarkan 100% bahan kering adalah 96,95%. Hasil analisis kadar serat kasar dalam praktikum adalah 3,05% dan berdasarkan 100% bahan kering adalah 96,95% serta setelah dikonversikan kedalam 100% BK adalah 3,1839%. Hasil analisis kadar serat kasar dalam praktikum adalah 3,05% dan berdasarkan 100% bahan kering adalah 96,95% serta setelah dikonversikan kedalam 100% BK adalah 3,1839%.
DAFTAR PUSTAKA
Anggorodi, R. 1997. Ilmu Makanan Ternak Umum. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Blakely, J. dan D.H. Bade. 1994. Ilmu Peternakan. Gadjah Mada University Press, Yogjakarta. Church, D. C. 1991. Livestock Feeds and Feeding 3rd Edition Regents/ Prentice Hall, New Jersey. Hartadi, H., S. Reksohadiprojo, Tillman, A.D. 1997. Tabel Bahan Pakan Untuk Indonesia. Universitas Gajah Mada Press. Yogyakarta. Kartadisastra, H. R. 1997. Penyediaan dan Pengelolaan Pakan Ternak Ruminansia. Penerbit Kanisius, Yogyakarta. Lubis, D.A. 1992.Ilmu Makanan ernak. PT. Pembangunan, Jakarta Mc. Donald, R. A. Edwards, J. F. Breenhalen. 1978. Animal Nutrition. 2nd Ed., Longman, London. Murtidjo, B. A. 1987. Pedoman Meramu Pakan Unggas. Kanisius, Yogyakarta. Prawirokusumo, S. 1994. Ilmu Gizi Komparatif. Penerbit BPFE, Yogyakarta. Rasyaf, M. 1990. Bahan Makanan Unggas di Indonesia. Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, Bogor. Srigandono, B. 1996. Kamus Istilah Peternakan Edisi kedua. Gadjah Mada Press, Yogyakarta Sutardi, T. 1980. Landasan Ilmu Nutrisi. Departemen Ilmu Makanan Ternak Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, Bogor. (Tidak diterbitkan) Tillman, A.D., H. Hartadi, S. Reksohadiprodjo, S. Prawirokusumo, S. Lebdosoekojo. 1991. Ilmu Makanan Ternak Dasar Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta. Tillman, A.D., Hartadi, S. Reksohadiproji, S. Prawirokusumo dan S. Lebdosutjoko. 1998. Ilmu Makanan Ternak Dasar. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Lampiran 1. Perhitungan Analisis Kadar Air
Sampel Sesungguhnya = Berat sampel (ktas mnyk sisa krtas mnyak sblm dgnkn) Sampel A Sampel B = 1,0886 - (0,2265 0,2958) = 1,1579 = 1,0513 (0,2737 0,2709) = 1,0485x 100%
% Kadar air =
Sampel A
= 13,5526+1,0886-14,5873 x 100% 1,1579 = 4,65%
Sampel B
= 14,1956+1,0513-15,2062 x 100% 1,0485 0,9825 = 3,88%
Rata-rata kadar air
= 4,65% + 3,88% 2 = 4,2605%
Bahan Kering
= 100% - Kadar Air (%) = 100% - 4,2605% = 95,795%
Konversi 100 % BK = % Kadar Air x 100% %BK = 4,2605 x 100% 95,795 = 4,4475%
Lampiran 2. Perhitungan Analisis Kadar Abu Keterangan: X = Berat cawan porselin setelah dioven pada suhu 105-1100C selama 1 jam dan dieksikator selama 15 menit (gr) Y = Berat sampel bahan pakan dan cawan sebelum ditanur (gr) Z = Berat sampel bahan pakan dan cawan porselin setelah ditanur pada suhu 4006000C selama 2 jam (gr)% Kadar Abu
= = 12,5914 12,3807 x 100% 1,0011 = 21,05%
x 100%
Sampel A
Sampel B
= 15,4250 15,1983 x 100% 1,0782 = 21,026%
Rata-rata kadar abu = 21,05% + 21,026 2 2 = 21,038% %BK = 100% - %KA = 100% - 21,038 = 78,968% Konversi 100 % BK = %Kadar Abu x 100% %BK = 21,038 x 100% 95,795 = 21,96%
Lampiran 3. Perhitungan Analisis Kadar Protein Kasar Keterangan : X = Berat sampel yang dimasukan ke dalam labu destruksi (gr) Y = Jumlah titer untuk blanko (ml) Z = Jumlah titer titrasi distilat (ml) N = Normalitas Na OH (N)% Kadar Protein Kasar
=
x100%
Sampel A = (40,5 0,55)x0,11x0,014x 100% 1,0058 = 38,23 % Sampel B = (41 0,55)x0,11x0,014x 100% 1,0051 = 38,74 % %BK = 100% - %PK = 100% - 3,63% = 96,37%
Konversi 100% bahan kering = 100 x %PK %BK = 100 x 3,63 95,795 = 3,5075%
Lampiran 4. Perhitungan Analisis Kadar Lemak Kasar Keterangan : A = Berat kertas saring setelah digunakan B = Berat kertas saring dan sampel setelah dioven C = Berat sampel
%KA = Sampel A = = 1,81% x 100%
x 100%
Sampel B = = 50,75 %
x 100%
Rata-rata KA = = 11,324%
Rata-rata LK
= = -0,0004%
Lampiran 5. Perhitungan Analisis Kadar Serat Kasar Kadar serat kasar =
x 100%
Sampel A
= 22,9355 - 21,5163 1,3188 x 100% 21,5053 = 0,46% = 19,9176 - 18,0042 1,3287 x 100% 18,0004 = 3,2% 2 = 1,83%
Sampel B
Rataan % Kadar Serat Kasar = 0,46% + 3,2%
Konversi 100% BK
= 100 75,3% = 2,43%
x 1,83%
Lampiran 6. Perhitungan Analisis Kadar BETN 6.1. Perhitungan Analisis Kadar BETN berdasarkan bahan kering udara Kadar BETN = 100% - (%air + %kadar abu + %kadar PK + %kadar LK + %kadar SK) = 100% - (4,2605 + 21,038 + 3,63 + -0,0004 + 3,05) = 68,0219% 6.2. Perhitungan Analisis Kadar BETN berdasarkan 100% Bahan Kering Kadar BRTN= 100% - % PK - % LK - % SK - % Abu = 100% - (3,5075 + 11,324 + 3,1839 + 21,96) = 60,0246%