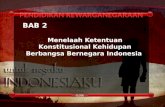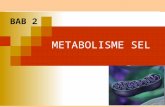Bab 2
Transcript of Bab 2
7
II.
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penyakit hati kronis Penyakit hati kronis adalah sekelompok kelainan hati. Penyakit ini memperlihatkan proses peradangan dan nekrosis yang aktif dan kronik tanpa penyembuhan yang berlanjut lebih dari enam bulan sejak mulai timbul keluhan dan gejala penyakit. Penyakit hati kronis disebabkan oleh bermacam-macam etiologi. Selain itu ditandai oleh berbagai tingkat peradangan dan nekrosis pada hati yang berlangsung terus-menerus (Sujono, 2002). Perbandingan penderita penyakit hati kronis laki-laki dengan wanita adalah 1,6 : 1. Penyakit hati kronis ini paling banyak diderita laki-laki dengan umur 30 59 tahun, dengan puncaknya sekitar 40 49 tahun. Di Indonesia, angka prevalensi secara pasti belum diketahui karena faktor geografi yang sangat luas. Menurut WHO, pada tahun 2003 prevalensi penyakit hati kronik di Indonesia antara 1- 2,4%. Jumlah tersebut sama dengan prevalensi di Australia dan Amerika Serikat. Di Amerika prevalensi pada tahun 2001 menurut data NCHS (National Center for Health Statistics) ada sekitar 13,2/100.000 laki laki dan 6,2/100.000 perempuan meninggal akibat sirosis dan penyakit hati kronis. Data yang sama menyebutkan sekitar 9,3/100.000 orang kulit hitam dan 9,6 orang kulit putih meninggal akibat penyakit yag sama. Rata rata jumlah peduduk Amerika yang meninggal akibat sirosis dan penyakit hepar kronis adalah sekitar 27.035 tiap
tahunnya (NCHS, 2003). Penderita penyakit hati kronis semakin meningkat tiap tahunnya. Menurut penelitian Levi et al., dari 38 Negara sejak tahun 1955 1990 angka rata rata kematian tertinggi akibat sirosis yakni sekitar 60/100.000 laki laki dan 15/100.000 perempuan diperoleh dari Negara Chile dan Mexico. Sementara Amerika, Kanada dan Amerika latin lainnya sekitar 5-17/100.000 laki laki dan 3-5/100.000 perempuan. Penyebab penyakit hati kronis dapat berbeda-beda diantaranya akibat infeksi hepatitis virus, terutama hepatitis virus B dan hepatitis virus C. Di Amerika Serikat, penyebab yang paling dominan adalah penyalahgunaan alkohol. Pada usia 45-65 tahun, penyakit hati kronis akibat infeksi virus merupakan penyebab kematian ketiga, setelah penyakit jantung dan kanker (Gish, 2003; Sujono, 2002). Etiologi penyakit hati kronis dapat diklasifikasikan berdasarkan respon peradangan yang berlangsung lebih dari enam bulan. Klasifikasinya adalah : 1. Infeksi virus Hepatitis virus merupakan penyebab paling dominan terjadinya penyakit hati kronis. Para ilmuwan mengetahui tujuh virus yang dapat menyebabkan hepatitis. Kemajuan di bidang biologi molekuler telah membantu pengenalan dan pengertian patogenesis dari tujuh virus penyebab hepatitis sebagai manifestasi penyakit utama. Virus-virus tersebut disebut virus hepatotropik.
9
Virus-virus tersebut ditandai dengan urutan abjad yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan terakhir virus TT. Virus-virus tersebut dinamakan HAV (Hepatitis A Virus), HBV (Hepatitis B Virus), dan seterusnya. Virus-virus lain yang juga memberi gejala hepatitis sebagai bagian dari gejala klinisnya, bukan disebut virus hepatotropik. Seperti virus herpes simplex (HSV), cytomegalo (CMV), epsteinbarr, varicella, rubella, adeno, entero, dan HIV. Lebih dari 90% kasus hepatitis disebabkan HAV, HBV dan HCV (Gish, 2003; Sujono, 2002). Menurut onsetnya hepatitis virus dapat berlangsung akut maupun kronis. 1. Hepatitis virus akut : Hepatitis yang terjadi saat virus tidak mampu merusak sistem imun tubuh dan bertahan beberapa minggu dan mengalami penyembuhan kurang dari enam bulan. 2. Hepatitis virus kronis : Hepatitis yang memperlihatkan proses peradangan dan nekrosis yang aktif dan kronik tanpa penyembuhan yang berlanjut lebih dari enam bulan sejak mulai timbul keluhan dan gejala penyakit. 2. Intoksikasi akibat obat-obatan dan alkohol (Hepatotoksik) Beberapa obat-obatan (metildopa, isoniazid, nitrofurantoin, dan
acetaminophen) serta zat kimia dapat menyebabkan terjadinya kerusakan fungsi sel hati secara akut dan kronis. Kerusakan hati secara akut akan berakibat nekrosis atau degenerasi lemak. Sedangkan kerusakan kronik akan berakibat sirosis. Pemberian obat-obatan hepatotoksik secara berulang dalam jangka waktu panjang dan terus menerus akan menginduksi terjadinya
kerusakan sel-sel stelata, kemudian terjadi kerusakan hati yang merata, dan akhirnya dapat terjadi fibrosis, sirosis dan karsinoma hati . Zat hepatotoksik yang berperan adalah alkohol. Efek yang nyata dari etil-alkohol adalah penimbunan lemak dalam hati (Sujono, 2002).
3. Genetik (Hemokromatosis) dan Penyakit Wilson (Friedman, 2000) 1. Hemokromatosis Ada 2 kemungkinan timbulnya hemokromatosis, yaitu : a. Sejak dilahirkan, penderita mengalami kenaikan absorpsi dari Fe. b. Didapat setelah lahir (akuisita), misalnya dijumpai pada penderita dengan penyakit hati alkoholik. Bertambahnya absorpsi dari Fe, kemungkinan menyebabkan timbulnya penyakit hati kronis dan sirosis. 2. Penyakit Wilson Suatu penyakit yang jarang ditemukan, akibat penimbunan tembaga yang abnormal, biasanya terdapat pada orang-orang muda dengan ditandai penyakit hati kronis dan sirosis, degenerasi ganglia basalis dari otak, dan terdapatnya cincin pada kornea yang berwarna coklat kehijauan
11
disebut Kayser Fleiscer Ring. Penyakit ini diduga disebabkan defisiensi bawaan dan sitoplasmin. 4. Gangguan Imun Penyakit yang ditimbulkan karena adanya perlawanan terhadap jaringan tubuh sendiri. Misalnya pada hepatitis autoimun, aktivitas imun yang abnormal menyebabkan peradangan dan penghancuran sel-sel hati yang progresif sehingga terjadi peradangan kronis (Sherlock, 2001). 5. Kanker Misalnya hepatoseluler karsinoma (kanker hati). Kanker hati dapat disebabkan oleh senyawa karsinogenik diantaranya aflatoksin, polivinil kloride, dan virus. HVB dan HVC maupun sirosis dapat berkembang menjadi kanker hati (Iredale, 2003). 6. Kriptogenik Penyakit hati kronis yang penyebabnya tidak dapat diidentifikasi. Penderita ini sebelumnya tidak menunjukan tanda-tanda hepatitis atau penggunaan alkohol, sehingga kelompok ini dimasukan ke dalam kelompok penyakit hati kronis kriptogenik (Sherlock, 2001).
B. Fibrosis hepar
Fibrosis adalah respon proses penyembuhan luka yang melibatkan beberapa komponen sel seperti, matrik ekstraseluler (extracellular matrix), dan sitokin. Selama proses penyembuhan tadi, sel stelata hepar yang merupakan sel fibrogenik utama memegang peranan penting dalam proses penyembuhan. Aktivasi sel stelata tersebut merupakan awal terjadinya fibrosis hepar melalui komplek jaringan inter dan intraseluler. Fibrosis hepar merupakan akibat yang paling berat pada penyakit hati kronis. Penyebab fibrosis hepar sama seperti penyebab terjadinya penyakit hati kronis dan hampir 90% akibat infeksi HBV dan HCV (Moreira, 2007; Friedman, 2000). Saat ini fibrosis dan sirosis bukan merupakan kondisi yang irreversible seperti pendapat para ahli terdahulu. Namun menjadi kondisi yang reversible yang dibuktikan secara nyata dengan berhasilnya pengobatan terhadap penderita hepatitis C kronis, hemokromatosis dan penyalahgunaan alkohol (Bruce, 2008). Mekanisme reversible ini dapat terjadi melalui pengendalian aktivasi dan degradasi dari sel stelata hepar (Moreira, 2007; Friedman, 2000). Patofisiologi terjadinya fibrosis adalah nekrosis pada hepar yang menyebabkan kolaps lobulus hepar, serta terjadi pembentukan septum jaringan ikat yang difus, dan pertumbuhan nodul regeneratif sel-sel hepar (Sherlock, 2001). Nekrosis fokal akan diikuti oleh fibrosis fokal (Iredale, 2003). Kematian sel akan diikuti oleh pembentukan nodul-nodul yang akan merusak arsitektur hepar dan akan berkembang ke arah sirosis dan karsinoma hati (Friedman, 2000). Hepar yang normal memiliki matrik jaringan penghubung yang terdiri dari
13
kolagen tipe IV, laminin, heparan sulfat, protoglikan dan fibronektin. Matrik ini terletak di membran basal (Iredale, 2003). Adanya perlukaan pada hepar mengakibatkan peningkatan matrik ekstraselular yang mengandung kolagen pembentuk fibrin (tipe I dan III) yang dikenal sebagai proteoglikan, fibronektin, asam hialuronat, dan matrik glikokonjugasi (Friedman, 2000 dan Sherlock, 2001). Bukti-bukti penelitian terakhir telah mendukung hipotesa bahwa jalur akhir utama proses fibrosis dimediasi oleh sel stelata hepar. Adanya perlukaan hepar oleh pelbagai etiologi akan mengaktivasi sel stelata. Pada aktivasi ini terjadi peralihan dari keadaan diam menjadi berploriferasi, bersifat fibrogenik dan kontraktil. Pada daerah yang terluka sel stelata hepar akan mengalami transformasi menyerupai miofibrolas dan mengeluarkan protein kontraktil. Pada keadaan aktif sel ini akan berproliferasi dan akan menjadi sumber utama dari kolagen fibriler yang menandai adanya fibrosis dan sirosis (Nurjanah, 2006; Rockey, 2006; Safadi, 2004). Sitokin yang dilepaskan oleh sel-sel radang yang masuk ke daerah yang terluka, dan adanya kerusakan dan regenerasi hepatosit serta peran sel hepar lainnya akan mengaktivasi sel stelata sehingga sel stelata menjadi mediator sentral dalam penyembuhan luka (Wang et al., 1998). Studi terakhir menyatakan bahwa interleukin-10 telah diidentifikasi sebagai efektor anti inflamasi utama pada fibrosis hepar, terutama pada infeksi virus hepatitis C, dan Tumour necrosis factor berperan sebagai mediator proinflamasi. Sitokin
transforming growth factor -1 berperan dalam meningkatkan respon fibrogenik sel stelata hepar sehingga terjadi peningkatan produksi kolagen dan penurunan degradasi kolagen (Iredale, 2003). TGF-1 merupakan stimulus dominant terhadap produksi matriks ekstraseluler. TGF-1 meningkat pada fibrosis hepar. Kerja sitokin ini dipercepat oleh urokinase-type plasminogen activator. Pelepasan dan kerja sitokin ini dikontrol oleh protein intrasel. Percepatan sinyal sitokin ini mendasari respon terhadap perlukaan pada sel stelata (Battaller, 2004). Terjadi peningkatan ikatan TGF-1 terhadap reseptornya (tipe I dan II), sementara reseptor mRNA tipe II menurun selama aktifasi sel stelata (Friedman, 2000). Pada sel stelata teraktifasi waktu paruh kolagen (I)1 mRNA meningkat 20 kali lipat dibandingkan sel stelata yang inaktif (Safadi, 2004).
C. AST-platelet ratio index (APRI) AST-platelet ratio index (APRI) merupakan uji derajat fibrosis sederhana (simple fibrosis tests) berupa metode non invasif yang memberikan hasil sensitivitas dan spesifisitas tinggi terhadap derajat fibrosis dan sirosis. Selain itu APRI dapat memberikan efek komplikasi yang minimal bagi pasien hepatitis. APRI saat ini banyak digunakan di berbagai negara karena dianggap simpel dan ekonomis serta merupakan metode non invasif. Disamping itu dapat juga dijadikan alat scrrening (deteksi dini) pada pasien yang dicurigai menderita hepatitis kronis dan memprediksi telah terjadinya sirosis (Chen, 2004; Elloumi et
15
al., 2007). APRI digunakan dalam memprediksi derajat fibrosis yang bermakna dan derajat fibrosis lanjutan terhadap terjadinya sirosis dan karsinoma hati. Derajat fibrosis menggunakan klasifikasi skor METAVIR, yaitu tanpa fibrosis (F0), portal fibrosis (F1), septum fibrosis (F2), bridging fibrosis (F3), sirosis (F4). APRI ini merupakan kombinasi dari rasio AST dan platelet. Rasio keduanya diharapkan memberikan hasil yang lebih bermakna dalam memprediksi terjadinya fibrosis hepar, sirosis dan karsinoma hati (Dilshad et al., 2008). Kerusakan hati pada umumnya berdasarkan adanya kebocoran zat zat tertentu dari sel hati ke dalam peredaran darah. Sebagian besar dari tes ini merupakan tes yang mengukur aktivitas enzim dalam serum atau plasma. Aktivitas enzim yang sering dilakukan adalah aminotransferase yakni alanin aminotransferase (ALT) dan aspartat aminotransperase (AST). AST terdapat dalam sitoplasma mitokondria dalam bentuk beberapa isoenzim, sedangkan ALT hanya terdapat dalam sitoplasma (Ahmed, 2007; Dilshad et al, 2008). Enzim-enzim AST dan ALT akan meningkat bila terjadi kerusakan sel hati. Biasanya peningkatan ALT lebih tinggi daripada AST pada kerusakan hati yang akut, mengingat ALT merupakan enzim yang hanya terdapat dalam sitoplasma sel hati, dan sedikit di sel ginjal, sel jantung, dan otot skeletal.. Sebaliknya AST terdapat baik dalam sitoplasma maupun mitokondria sel hati, jantung, otot skeletal, ginjal, pankreas dan eritrosit akan meningkat lebih tinggi daripada ALT pada kerusakan hati yang kronis. Keadaan ini ditemukan pada kerusakan sel hati yang menahun (Sherlock, 2001).
Penentuan aktivitas AST dianggap sebagai tes yang lebih sensitif dan spesifik untuk kerusakan hati kronis, sedangkan kenaikan aktivitas ALT biasanya lebih sensitif pada kerusakan hati akut. Pada penyakit hati akut oleh virus, aktivitas ALT dan AST meningkat pada fase pra-ikterik dengan puncak aktivitas 7 sampai 10 hari sebelum kadar bilirubin memuncak. Peningkatan aktivitas dapat mencapai 20 hingga 50 kali batas rentang referen dengan ALT melebihi AST. Kemudian aktivitas enzim menurun setelah terjadi ikterik dan penyakit membaik, hingga mencapai angka normal lagi. Bila aktivitas normal atau bahkan menurun menunjukan terjadinya nekrosis hepatoseluler dan kegagalan hati. Pada keadaan ini aktivitas AST melebihi aktivitas ALT dan prognosis menjadi kurang baik. Bila aktivitas enzim transferase terutama AST normal atau atau bahkan menurun maka terjadinya hepatitis kronis atau sirosis hepatis dapat diperkirakan (Ahmed, 2007; Chen, 2008). Enzim AST pada manusia terdiri atas fraksi yang berasal dari mitokondria. Dalam keadaan normal 80% dari AST dalam hati orang dewasa berasal dari mitokondria. Pada penyakit hati kedua fraksi AST meningkat, tapi pada kerusakan hepatoseluler akut peningkatan fraksi sitoplasma lebih mencolok. Pada keadaaan dengan nekrosis jaringan yang berat fraksi mitokondria yang lebih tinggi. Pada penderita hepatitis alkoholik aktivitas AST yang berasal dari mitokondira lebih tinggi dan peningkatan tersebut disebabkan oleh kerusakan sel hati dan induksi enzim oleh alkohol (Sherlock, 2001). Platelet atau trombosit merupakan zat-zat pembekuan darah yang dihasilkan di hepar dan limpa. Pembentukan platelet sangat dipengaruhi oleh
17
trombopoietin (TPO). TPO merupakan sitokin yang berperan sebagai regulator utama dalam proses trombopoiesis, bekerja menstimulasi sumsum tulang sehingga terjadi proliferasi, diferensiasi, dan pematangan sel-sel progenitor. TPO terutama dihasilkan pada sel hapatosit (95%), sedikit pada ginjal, limpa, paru, sumsum tulang, dan otak. Sehingga ketika terjadi gangguan pada hati yang kronis maka kadar TPO yang bekerja dengan cara menstimulasi megakarositopoiesis dan maturasi trombosit menjadi berkurang dan menurun dan terjadi trombositopenia. Mekanisme penurunan platelet pada penyakit hati kronis akibat adanya pooling dan percepatan penghancuran trombosit akibat pembesaran limpa
(hipersplenisme) (Made, 2008; Akyuz, 2007). Pada keadaan penyakit hati kronis dan terjadi perlukaan hati maka kadar platelet dalam darah akan terganggu dan mengalami penurunan. Penurunan kadar platelet disebut trombositopenia. Trombositopenia terjadi bila kadar trombosit