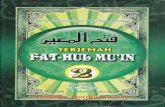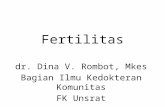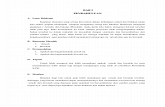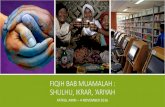as-ariyah
Transcript of as-ariyah
BAB I
PAGE 32
BAB I
PENDAHULUANA. Latar Belakang MasalahPerbedaan pendapat merupakan salah satu fenomena yang telah ada sejak terbentuknya komunitas manusia, sekecil apapun komunitas itu. Perbedaan tersebut dapat meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk agama dan keyakinan. Asy-Syahrastani (w. 458 H) dalam bukunya, al-Milal wa an-Nihal menyebutkan sekian perbedaan pendapat yang cukup penting antara sahabat-sahabat Nabi saw. sejak beliau sakit sampai beberapa waktu setelah wafatnya. Adalah suatu keanehan bagi Harun Nasution, bahwa Islam sebagai suatu agama, persoalan yang pertama-tama muncul dan yang melibatkan semua umat Islam serta telah mengganggu perjalanan sejarah Islam itu sendiri, justru bermula dari masalah politik, dan bukan dalam masalah teologi. Tetapi kemudian masalah politik itu meningkat dan berkembang menjadi atau bermuara pada masalah teologi, sehingga pada akhirnya, dalil-dalil teologi dijadikan pembenaran (legitimasi) bagi persoalan politik yang muncul lebih dahulu. Cikal bakal masalah politik itu berawal pada tahun 632 M, ketika Nabi Muhammad saw. wafat, tanpa meninggalkan wasiat atau alamat tentang figur atau siapa pengganti beliau. Di lain hal, umat Islam seakan-akan tidak siap secara politis ditinggalkan oleh Nabi. Masyarakat di Madinah sibuk memikirkan siapa pengganti Nabi sebagai kepala negara yang baru lahir itu, sehingga masalah pemakaman Nabi menjadi masalah kedua. Mulai sejak itulah, muncul persoalan baru yang sekaligus mendesak untuk dipikirkan umat Islam yaitu masalah khilfah. Berbagai polemik, friksi dan persoalan politik yang terjadi, akhirnya menuntun kepada munculnya persoalan-persoalan teologi yang lebih rumit, yaitu apa tanda atau ciri keislaman dan kekafiran, sehingga dapat ditentukan siapa yang kafir dan bukan, dan lebih lanjut, apakah orang yang sudah dianggap kafir itu boleh dibunuh(dihalalkan darahnya) atau terpelihara. Ketika mencoba menjawab berbagai persoalan di atas, timbullah tiga aliran klasik dalam teologi Islam, yaitu: Aliran Khawarij, Murjiah, dan Muktazilah. Muktazilah memperkenalkan pemakaian rasio ke dalam lapangan teologi Islam, sehingga teologi Muktazilah mempunyai corak teologi rasional atau teologi liberal. Aliran Muktazilah ini mendapat reaksi dari aliran yang muncul kemudian yang dipelopori oleh Ab al-Hasan al-Asyar dan dikenal sebagai aliran tradisional.
Seperti itulah, di kalangan kaum muslimin telah terjadi perbedaan pendapat yang melahirkan berbagai mazhab dalam aspek-aspek; itiqad (keyakinan), politik dan fikih. Secara garis besarnya ada dua kategori perbedaan pendapat tersebut. Pertama, perbedaan tidak sampai menyetuh inti agama Islam. Perbedaan ini tidak menyangkut masalah keesaan Tuhan, kesaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah, turunnya Alquran dari sisi Allah, serta Alquran itu mukjizat Nabi terbesar, dan seluruhnya diriwayatkan secara mutawtir dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perbedaan itu tidak mengenai kewajiban-kewajiban yang prinsipil, seperti shalat, zakat, haji, dan puasa dan tidak pula mengenai cara melaksanakannya. Kedua, perbedaan yang menyentuh masalah akidah dan politik.
B. Rumusan MasalahBerdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai objek kajian dalam makalah ini ialah sebagai berikut;
1. Bagaimana sejarah munculnya Aliran Asyariyah? 2. Siapa Abu al-Hasan al-Asyari dan bagaimana doktrin-doktrin teologinya? 3. Siapa sajakah tokoh-tokoh penting aliran al-Asyariyah?4. Bagaimana perkembangan aliran Asyariah sebagai aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah?5. Bagaimana pengaruh aliran Asy`ariyah di dunia Islam?BAB II
PEMBAHASAN
A. Sejarah Munculnya Aliran Asyariyah
Teologi Asyariah muncul karena tidak terlepas dari, atau malah dipicu oleh situasi sosial politik yang berkembang pada saat itu. Teologi Asyar muncul sebagai teologi tandingan dari aliran Muktazilah yang bercorak rasionil. Aliran Muktazilah ini mendapat tantangan keras dari golongan tradisionil Islam terutama golongan Hanbali. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Pada tahun 827 Khalifah Abbasiyah, al-Makmun, menerima doktrin Muktazilah secara resmi, dan dilanjutkan pada pemerintahan dua khalifah setelahnya. Orang-orang yang teguh memegang tradisi, khususnya Ahmad bin Hanbal disiksa bahkan lebih dari itu, orang-orang yang tidak memahami defenisi dogmatis Muktazilah yang cerdas atau menolak menerima mereka, dan kadang-kadang sebagian besar dianggap kafir.
Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Makmun, serangan Muktazilah terhadap para fuqah dan muhadditsn semakin gencar. Tak seorang pun pakar fiqh yang populer dan pakar hadis yang mashur luput dari gempuran mereka. Serangan dalam bentuk pemikiran, disertai dengan penyiksaan fisik oleh penguasa dalam bentuk suasana al-mihnah (inkuisisi). Banyak para tokoh dan ulama yang menjadi panutan umat menjadi korban gerakan mihnah, mulai dari penyiksaan fisik, pemenjaraan bahkan sampai pada hukuman mati.
Sebagai akibat dari hal itu, timbul kebencian masyarakat terhadap Muktazilah, dan berkembang menjadi permusuhan. Masyarakat tidak senang dengan hasutan-hasutan mereka untuk melakukan inkuisisi (mihnah) terhadap setiap imam dan ahli hadis yang bertaqwa. Isu sentral yang menjadi topik mihnah waktu itu adalah tentang Alquran sebagai mahluk bukan bukan kalamullah yang qadm.Keadaan berbalik setelah Al-Mutawakkil naik menduduki tahta kekhalifahan. Setelah kurun pemerintahan khalifah Al-Makmun, Al-Mutasim dan Al-Wasiq dari Dinasti Abbasiyah (813M-847M) paham Muktazilah mencapai puncaknya. Akhirnya Al-Mutawakkil membantalkan pemakaian aliran Muktazilah sebagai mazhab negara di tahun 848 M. Dengan demikian selesailah riwayat mihnah yang ditimbulkan kaum Muktazilah dan dari ketika itu mulailah menurun pengaruh dan arti kaum Muktazilah.
Beliau sebagai khalifah menjauhkan pengaruh Muktazilah dari pemerintahan. Sebaliknya dia mendekati lawan-lawan mereka, dan membebaskan para ulama yang dipenjarakan oleh khalifah terdahulu.
Pada akhir abad ke 3 Hijriah muncul dua tokoh yang menonjol, yaitu Ab al-Hasan al-Asyar di Bashrah dan Ab Manshr al-Mtrid di Samarkand. Keduanya bersatu dalam melakukan bantahan terhadap Muktazilah, kendatipun diantara mereka terdapat pula perbedaan. Selanjutnya, yang akan dibicarakn hanyalah mengenai al-Asyari yang merupakan tokoh sentral dan pendiri aliran Asyariyah.
B. Abu al-Hasan al-Asyari dan Doktrin-Doktrin Teologinya
Nama lengkap Al-Asyari ialah Ab al-Hasan Al bin Ismil bin Ab Basyar Ishq bin Slim bin Ismil bin Abdillah bin Ms bin Bill bin Abi Burdah Amir bin Ab Ms al-Asyari. lahir di Basrah pada 260 H/875 M. Ketika berusia lebih dari 40 Tahun, ia hijrah ke kota Baghdad dan wafat di sana pada tahun /324 H/935 M. Abu al-Hasan al-Asy'ari pada mulanya belajar membaca, menulis dan menghafal Alquran dalam asuhan orang tuanya, yang kebetulan meninggal dunia ketika ia masih kecil. Selanjutnya dia belajar kepada ulama Hadis, Fiqh, Tafsir dan bahasa antara lain kepada al-Saji, Abu Khalifah al-Jumhi, Sahal Ibn Nuh, Muhammad Ibn Ya'kub, Abdur Rahman Ibn Khalf dan lain-lain. Demikian juga ia belajar Fiqih Syafi'i kepada seorang faqih: Abu Ishak al-Maruzi (w.340 H./951 M.) seorang tokoh Muktazilah di Bashrah. Sampai umur 40 tahun ia selalu bersama Abu Ali al-Jubbai, serta ikut berpartisipasi dalam mempertahankan ajaran-ajaran Muktazilah.
Al-Asyar adalah murid dan belajar ilmu kalam dari seorang tokoh Muktazilah, yaitu Ab Ali al-Jubba, malah Ibnu Asakir mengatakan bahwa al-Asyar belajar dan terus bersama gurunya itu, selama 40 tahun, sehingga al-Asyar pun termasuk tokoh Muktazilah. Dan karena kepintaran serta kemahirannya, ia sering mewakili gurunya itu dalam berdiskusi. Namun pada perkembangan selanjutnya, al-Asyar menjauhkan diri dari pemikiran uktazilah dan selanjutnya condong kepada pemikiran para fuqaha dan ahli hadis.
Ahmad Amin dalam Zuhr al-Islm menyebutkan bahwa mazhab al-Asyari itu adalah mazhab Muktazilah yang telah ia adakan penyesuaian-penyesuaian pada berbagai persoalan, dan ia berhasil manarik pengikut yang banyak serta sangat sukses melahirkan mazhab baru. Keberhasilan al-Asyari yang cemerlang dan cepat dalam menarik pengikut, tidak lain karena pada saat itu Muktazilah sedang dijauhi dan tidak disukai orang, akibat tindakan mihnah yang dilakukan penguasa yang berpihak kepada Muktazilah. Disamping itu, al-Asyari sendiri merupakan seorang yang berwawasan luas, berpandangan teliti, dan sekaligus penulis yang baik sekaligus produktif. Kedua karyanya al-Ibanah an Usul al-Diyanah dan al-Luma fi al-Rad ala Ahl al-Zaigh wa al-Bida membuktikan keterampilan tersebut. Lalu, mengapa al-Asyari meninggalkan gurunya dan paham Muktazilah, serta membentuk paham dan mazhab baru? Ada beberapa riwayat yang menceritakan hal tersebut, antara lain:
Ibnu Asakir menceritakan bahwa pada suatu malam al-Asyari bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad Saw, lalu Nabi menyuruhnya meninggalkan paham Muktazilah, dan supaya ia membela sunnahnya. Awal peristiwa ini, bermula ketika al-Asyari bertanya kepada gurunya waktu belajar. Jawaban sang guru tidak tidak memuaskan al-Asyari, sehingga ia menjadi ragu-ragu dan ingin mencari kepuasan.
Versi lain diceritakan bahwa, hal yang mendorong al-Asyari meninggalkan Muktazilah dan mengkaji ulang alasan-alasan mereka, sehingga beliau membuktikan kesesatan mereka ialah, al-asyari bermimpi bertemu Rasulullah pada malam awal kesepuluh bulan ramadhan, dan berulang pada pertengahannya, dan malam sepuluh terakhir dari bulan ramadhan dan Rasulullah berkata kepada beliau Hai Ali bantulah sunnah yang disandarkan kepadaku karena itulah kebenaran yang hakiki.
Al-Subki dan Ibnu Khalkan menukilkan bahwa dalam rangka mempersiapkan diri untuk menjawab pemikiran aliran Muktazilah, al-Asyari untuk sementara mengurung diri di rumahnya selama 15 hari, merenung dan mencoba membanding-bandingkan dalil-dalil kedua kelompok aliran yang bertentangan (Muktazilah dan ulama Sunni). Kemudian ia keluar menemui masyarakat dan mengundang mereka untuk berkumpul. Selanjutnya, pada suatu hari jumat di Bashrah ia naik mimbar dan berkata,Barang siapa yang telah mengenalku, maka sebenarnya dia telah mengenalku. Dan barang siapa yang belum mengenalku, maka kini saya memperkenalkan diri. Saya adalah fulan ibnu fulan. Saya pernah mengatakan bahwa Alquran adalah makhluk, bahwa Allah tidak terlihat oleh indra penglihatan kelak pada hari kiamat, dan abhwa perbuatan-perbuatan saya yang tidak baik, saya sendirilah yang melakukannya. Kini saya bertobat dari pendapat seperti itu, serta siap sedia untuk menolak pendapat Muktazilah, dan mengungkap kelemahan mereka. Selama beberapa hari ini saya telah menghilang dari hadapan anda sekalian, karena saya sedang berpikir. Menurut pendapat saya, dalil-dalil kedua kelompok itu seimbang. Kemudian saya memohon petunjuk kepada Allah, maka Allah memberikan petunjuk kepada saya untuk meyakini apa yang tertera dalam kitab-kitab saya. Saya akan melepaskan apa yang pernah saya percayai, sebagaimana saya menanggalkan baju ini.
Disamping itu, al-Syahrastani menceritakan lain lagi. Katanya, pernah terjadi munazharah antara al-Asyari denga gurunya al-Jubbai tentang masalah al-Shalah dan al-Ashlah. Keduanya berada pada pandangan yang sangat berlawanan, sehingga terlibat pada perdebatan yang sengit. Al-Asyari berpihak kepada pendapat golongan yang memercayai adanya sifat bagi Allah. Dan ia menopang argumentasinya dengan metode ilmu kalam, dan jadilah kemudian pendapat al-Asyari itu mazhab Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah dan melekatlah cap shifatiyyah pada golongan Asyariyah.
Sebab klasik yang biasa disebut perpisahan dia dengan gurunya karena terjadinya dialog antara keduanya tentang salah satu ajaran pokok Muktazilah, yaitu masalah "keadilan Tuhan." Muktazilah berpendapat,"semua perbuatan Tuhan tidak kosong dari manfaat dan kemashlahatan. Tuhan tidak menghendaki sesuatu, kecuali bermanfaat bagi manusia, bahkan Dia mesti menghendaki yang baik dan terbaik untuk kemashlahatan manusia. Paham ini di sebut al-Shalah wa 'l-Ashlah.
Dialog tersebut berlangsung sebagai berikut:
Al-Asy'ari : Bagaimana pendapat tuan tentang nasib tiga orang bersaudara setelah wafat; yang tua mati dalam bertaqwa; yang kedua mati kafir; dan yang ketiga mati dalam keadaan masih kecil.
Al-Jubba'i : yang taqwa mendapat terbaik; yang kafir masuk neraka; dan yang kecil selamat dari bahaya neraka.
Al-Asy'ari : Kalau yang kecil ingin mendapatkan tempat yang lebih baik di Sorga, mungkinkah?
Al-Jubba'i : Tidak, karena tempat itu hanya dapat dicapai dengan jalan ibadat dan kepatuhan kepada Tuhan. Adapun anak kecil belum mempunyai ibadat dan kepatuhan kepada-Nya.
Al-Asy'ari : Kalau anak kecil itu mengatakan kepada Tuhan:itu bukan salahku. Sekiranya Engkau bolehkan aku terus hidup, aku akan mengerjakan perbuatan baik seperti yang dilakukan oleh yang taqwa itu.
Al-Jubba'i : Allah akan menjawab kepada anak kecil itu, Aku tahu, jika engkau terus hidup, engkau akan berbuat maksiat dan engkau akan mendapat siksa; maka Saya (Allah) matikan engkau adalah untuk kemaslahatanmu.
Al-Asy'ari : Sekiranya saudaranya yang kafir mengatakan, "Ya Tuhanku Engkau ketahui masa depanku sebagaimana Engkau ketahui masa depannya, mengapa Engkau tidak jaga kepentinganku?
Al-Jubba'i menjawab,"Engkau gila, (dalam riwayat lain dikatakan, bahwa Al-Jubba'i hanya terdiam dan tidak menjawab).
Dalam percakapan di atas, al-Jubba'i, jagoan Muktazilah itu, tampaknya dengan mudah saja dapat ditumbangkan oleh al-Asy'ari. Tetapi dialog ini kelihatannya hanyalah sebuah ilustrasi yang dibuat para pengikut al-Asy'ari sendiri untuk memperlihatkan perbedaan logikanya dengan logika orang-orang Muktazilah.
Bagi Muktazilah, si anak kecil tentu tidak akan mengajukan protes kepada Allah, karena dia sendiri tahu, bahwa sesuai dengan keadilan Tuhan, tempat yang cocok untuknya memang di sana. Kalau Tuhan menempatkan anak kecil sederajat dengan tempat orang yang taqwa, tentu dia sendiri akan merasakan bahwa Tuhan sudah tidak adil lagi terhadap dirinya. Sebab, tempatnya memang bukanlah seharusnya sederajat dengan orang-orang yang taqwa. Di alam akhirat, menurut Muktazilah, tidak ada lagi perdebatan tentang keadilan Tuhan. Disana, manusia sudah mendapati al-Wa'ad wa al-Wa'id. Dia sudah menepati janji. Yang taqwa mendapat sorga, yang kafir mendapat neraka, dan jika di sana terdapat yang meninggal dunia dalam keadaan masih kecil, baik anak-anak orang mukmin atau kafir, maka bagi mereka tidak ada alasan untuk disiksa, karena Tuhan Maha Suci dari penganiayaan.
Bagi yang kafir lebih tidak punya alasan lagi. Sebab, Tuhan lebih memperhatikan kemaslahatannya didunia. Tuhan tidak menghendaki kekafirannya. Berarti, jika ia kafir sama artinya dengan kehendak diri sendiri. Sementara, dia sendiri sudah tahu akibat kekafirannya, karena ia diberi akal dan petunjuk. Jadi, kalau yang kafir harus menyalahkan Tuhan atas kehendak dan perbuatannya sendiri, maka ia dianggap oleh memorandum suatu pemikiran yang tidak rasional.
Sebenarnya, untuk mengetahui sebab yang hakiki tentang berpindahnya al-Asyari dari Muktazilah, perlu diperhatikan kondisi yang ada waktu itu, baik yang berkaitan dengan perkembangan pemikiran keagamaan, maupun situasi sosial politik dan keadaan kekuasaan Sultan. Menurut al-Kautsari, al-Asyari melihat para fuqaha dan muhadditsin memfokuskan perhatian dalam memahami agama dengan dalil-dalil serta argumentasi yang berpijak pada tafsir, hadits, ijma dan qiyas. Disamping itu, para mutakallimin menfokuskan perhatian membela agama dengan senjata logika akal dan mengabaikan nash. Antara kedua kelompok ini terjadi pertentangan yang sangat tajam.. Kata al-Kautsari, maka mula-mula al-Asyari berusaha mendamaikan atau ishlah antara kedua pihak dengan mengajak mereka untuk kembali dari terlalu ekstrim, kepada jalan yang tengan yang adil.
Selanjutnya dijelaskan, al-Asyari berpendapat bahwa metode Muktazilah akan membawa Islam kepada kehancuran (al-dhimar), dan metode muhadditsin dan kawan-kawannya akan membawa Islam menjadi jumud dan mundur. Disamping itu, hal ini juga telah membuat umat Islam berpecah belah. Maka untuk kepentingan Islam dan kesatuan umat, alangkah idealnya bila kedua pihak mencari jalan keluar dan bertemu pada suatu mazhab yang merupakan jalan tengah yang dapat menyatukan hati, mengembalikan kesatuan umat, dengan mengindahkan nash dan aql sekaligus.
Al-Asyari sampai pada kesimpulan bahwa Alquran dan al-Sunnah tidak mengabaikan aql. Penggunaan aql dalam memahami dan membela syariah adalah suatu kemestian, bukan suatu kesesatan. Dalam masalah agama kita bisa menggunakan dalil aqli dan dalil naqli. Ada diantara masalah itu yang memerlukan dalil aqli, dan ada pula yang tak mungkin dipahami kecuali dengan dalil naqli, disamping ada juga yang memerlukan kedua macam dalil itu (aqli dan naqli).
Pemikiran al-Asy'ari yang asli baru dapat diketahui setelah ia menyatakan pemisahan dirinya dari Muktazilah dan pengakuannya menganut paham akidah salafiyah aliran Ahmad bin Hambal. Yaitu keimanan yang tidak didasari penyelaman persoalan gaib yang mendalam. Disisi lain, ia hanya percaya pada akidah dengan dalil yang ditunjuk oleh nash, dan dipahami secara tekstual sebagaimana yang tertulis dalam Kitab suci dan sunnah Rasul. Fungsi akal hanyalah sebagai saksi pembenar dan penjelas dalil-dalil al-Qur'an. Jadi akal terletak di belakang nash-nash agama yang tidak boleh berdiri sendiri. Ia bukanlah hakim yang akan mengadili. Spekulasi apapun terhadap segala sesuatu yang sakral dianggap suatu bid'ah. Setiap dogma harus dipercayai tanpa mengajukan pertanyaan bagaimana dan mengapa.
Sekarang permasalahannya ialah, sampai seberapa jauh al-Asy'ari meninggalkan ajaran-ajaran Muktazilah dan keikhlasannya terhadap ajaran Salafiyah. Untuk mengetahui ajaran-ajaran al-Asy'ari, kita dapat melihat pada kitab-kitab yang ditulisnya, terutama:
1. Maqalat al-Islamiyin, merupakan karangan yang pertama dalam soal-soal kepercayaan Islam. Buku ini menjadi sumber yang penting, karena ketelitian dan kejujuran pengarangnya. Buku ini terdiri -dari tiga bagian:
a. Tinjauan tentang golongan-golongan dalam Islam
b. Aqidah aliran Ashhab al-Hadits dan Ahl al-Sunnah, dan
c. Beberapa persoalan ilmu Kalam.
2. Al-Ibanah 'an Ushul al-Diyanah, berisikan uraian tentang kepercayaan Ahl al-Sunnah dan pernyataan penghargaannya terhadap persoalan-persoalan yang banyak dan penting. Dalam buku ini ia menyerang dengan pedas aliran Muktazilah.
3. Kitab al-Luma' fi al-Radd 'ala ahl al-Zaigh wa al-bida', berisikan sorotan terhadap lawan-lawannya dalam beberapa persoalan ilmu Kalam.
Posisi mazhab al-Asyari terhadap Muktazilah dapat terlihat dalam ungkapan al-Asyari sendiri pada pendahuluan kitabnya al-Ibanah yang maksudnya kira-kira sebagai berikut: Sebenarnya kebanyakan Muktazilah dan Qadariyah bertaklid kepada pemimpin dan pendahulu mereka. Mereka men-tawil-kan Alquran berdasarkan pendapat para pendahulu tersebut. Padahal Allah tidak memberikan otoritas kepada mereka untuk melakukannya, dan tidak menjelaskan dalilnya. Mereka tidak mengutip hadis Rasulullah, maupun peryataan ulama salaf. Mereka menentang riwayat sahabat tentang riwayat melihat Allah dengan indra penglihatan kelak pada hari kiamat. Padahal ada sejumlah hadis dari sanad yang berlainan dan mutawatir mengenai masalah itu.
Mereka juga mengingkari siksa kubur dan masalah orang-orang kafir yang disiksa dalam kubur. Padahal persoalan itu telah disepakati oleh para sahabat dan tabiin. Pendapat mereka bahwa Alquran adalah makhluk, sesungguhnya dekat dengan pendapat orang musyrik yang mengatakan Alquran itu tidak lain hanyalah perkataan manusia (Muhammad). Mereka beranggapan bahwa Alquran adalah seperti perkataan manusia. Mereka juga menetapkan dan meyakini bahwa hamba (manusia) menciptakan kejahatannya, suatu penetapan yang serupa dengan pendapat Majusi yang menetapkan adanya dua pencipta, yaitu pencipta kebaikan dan pencipta kejahatan.
Al-Asyari adalah pendiri suatu mazhab yang dikenal dengan nama Asyriyah atau Asyairah. Namun tidak selalu pemikiran para pengikutnya sejalan dengan pendapat al-Asyari. Beliau menyusun satu mazhab yang dimulai dengan membicarakan tentang Allah, sifat-sifat-Nya, huduts al-alam, problematika sifat-sifat pada umumnya, dan masalah al-kasb yang menjadi ciri khas al-Asyari.
Pendapat-pendapat Asyari dapat ditemui dalam kitab-kitab beliau; al-Ibanah an Ushul al-Diyanah, al-Luma fi al-Radd ala Ahl al-Zaig wa al-Bida, Istihsan al-Haudh fi Ilm al-Kalam, dan Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Mushallin. Kitab-kitab Asyari tersebut berisi penolakan-penolakan terhadap pendapat (pemikiran) lawan-lawannya, terutama Muktazilah. Ini adalah wajar, karena Asyari ingin memantapkan mazhabnya yang baru yang berbeda dengan Mutazilah, dan sekaligus untuk memuaskan para pengikut serta murid-muridnya. Dalam kitab al-Ibanah, al-Asyari lebih dahulu mengemukakan pokok-pokok pemikiran Ahl as-Sunnah wa al-Jamaah, yang diiringi dengan rincian penjelasan pendapat-pendapat tersebut. Ini utnuk membuktikan bahwa ia penyambung lidah dari golongan tersebut.
Dalam al-Ibanah, al-asyari tidak berbicara soal al-Kasb. Disana ia hanya bicara soal melihat Tuhan di akhirat, masalah khalq al-Quran, kemudian menegaskan hal-hal yang hanya diimani saja seperti apa tersebut dalam nash, misalnya al-istiwa, al-wajh, al-yadain, al-haudh, al-mizan, dan al-shirath. Dan dalam al-Luma, ia bicarakan tentang sifat-sifat, tentang al-kasb, al-tadil, dan al-tajwir, serta masalah-masalah iman dan imamah. Dalam al-Ibanah, ia terlihat lebih mementingkan pembicaraan dua masalah yaitu; khalq Alquran dan al-Ruyah, karena masalah inilah yang menyeret Ahmad ibnu Hanbal kepada mihnah. Dapat dikatakan bahwa ia ingin membela Imam Ahmad bin Hanbal lebih dahulu. Kemudian ia bicara soal al-kasb, dan al-tanzih, yang pembicaraannya memerlukan bantuan aql di samping al-nash.
Al-Asyari memulai pembicaraan tentang pokok aqidah yaitu wujud Allah. Untuk itu, al-Syahrastani, al-Asyari lebih dulu menegaskan huduts al-insan, atau manusia itu selalu berubah. Selagi dalam perut ibunya, berubah dari nuthfah, menjadi alaqah, selanjutnya menjadi mudhghah, dan akhirnya janin. Dan setelah lahir ke dunia, dari bayi berkembang menjadi anak-anak, terus menjadi remaja, kemudian dewasa, sampai tua, dan akhirnya meninggal. Perubahan tersebut pasti bukan karena perbuatan atau ciptaan manusia itu sendiri. Bukan pula oleh orang tua atau ibu bapaknya. Semua itu bermula dari pelaku yang qadim serta kuasa dan mampu melakukannya. Itulah Dia Allah Yang Maha Esa. Jadi Allah itu wajib al-wujud.
Abu Hasan al-Asyari berkata: apabila manusia mau memikirkan tentang kejadian dirinya dari apa dirinya diciptakan, kemudian berubah dari suatu proses ke proses yang lebih semurna, ia yakin bahwa dirinya bukan yang mengatur proses ini, dari yang sangat sederhana kepada yang lebih sempurna, maka ia memahami pasti Pengatur Yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui dan Maha Berkehendak. Tidak mungkin terjadi kejadian yang begitu rumit tanpa adanya pengatur dan bekasnya kelihatan apa ciptaan-Nya.
Lebih jauh, al-Asyari menjelaskan bahwa tak mungkin manusia itu yang mengubah-ubah dirinya dari nuthfah ke alaqah dan mudhghah, berdaging, bertulang dan berdarah, dari kanak-kanak menjadi remaja atau dari tua menjadi muda kembali. Semua kejadian atau proses ini kembali kepada mudabbir, pengatur, pelaku, dan pelaksana. Mustahil terjadi yang hadits tanpa adanya muhdits. Seperti halnya ada kain tanpa penenun, adanya bangunan tanpa pembangun, atau tulisan tanpa ada penulisnya. Menjelaskan hal ini al-Baghdadi mengatakan :
(Karena sesungguhnya tidaklah mungkin ada tulisan tanpa penulis, kain tanpa tukang tenun, bangunan tanpa tukang. Begitu pulalah tak mungkin ada hadits tanpa muhdits).
Namun, al-Asyari menafikan qadim-nya nuthfah, berbeda dengan para filosof yang menganggap qidam al-maddah. Alasan al-Asyari karena nuthfah itu bisa berubah dan berkembang dan itu adalah diantara ciri al-huduts. Lebih lanjut al-Asyari mengatakan,Tuhan yang mengadakan dan mengatur semua perubahan itu, pastilah Esa, atau hanya satu, tidak mungkin lebih dari satu. Karena kalaulah Dia lebih dari satu, akan terjadi ikhtilaf dan tamanu atau persaingan diantara mereka. Bagaimanapun kemungkinannya, tentu ada yang menang dan ada yang kalah. Yang menang, kuat, dan kehendak-Nya yang berlaku, itulah Tuhan, dan yang kalah,lemah, bukan Tuhan.
Sebagai penentang Muktazilah, sudah barang tentu al-Asy'ari berpendapat, bahwa Tuhan mempunyai sifat. Mustahil Tuhan sendiri merupakan pengetahuan ('Ilm). Yang benar,Tuhan itu mengetahui (Alim).Tuhan mengetahui dengan pengetahuanNya, bukanlah dengan Zat-Nya. Demikian pula bukan dengan sifat-sifat seperti, sifat hidup, berkuasa, mendengar dan melihat.
Disini terlihat, al-Asy'ari menetapkan sifat kepada Tuhan seperti halnya kaum Salafi. Namun cara penafsirannya cukup berbeda. Kaum Salafi hanya menetapkan sifat kepada Allah, sebagaimana teks ayat, tanpa melakukan pembahasan mendalam. Mereka hanya menerima arti dengan jalan kepercayaan, bahwa sifat-sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk-Nya. Lain halnya dengan al-Asy'ari, baginya arti sifat tidak jauh berbeda dengan pengertian sifat bagi Muitazilah. Bagi al-Asy'ari, sifat berada pada Zat, tetapi sifat bukan Zat, dan bukan pula lain dari Zat.
Mengingat dan menyaksikan betapa sempurna dan rapinya ciptaan dan perbuatan serta pengaturan Allah terhadap makhluk-Nya ini, maka al-Asyari menegaskan bahwa pastilah Allah itu punya sifat-sifat; al-ilm, al-qudrah, al-hayah, al-sama dan al-bashar, sekaligus dia alim, qadir, al-hayy, sami dan bashir. Kata al-Asyari,Makna alim menurutku bahwa Dia punya ilmu. Orang tidak berilmu bukanlah bernama 'alim. Al-Asyari memperkuat pendapatnya itu dengan mengutip ayat Q.S. al-Nisa (4:166)
((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( (((((((( (((((
Terjemahnya:
(mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu), tetapi Allah mengakui Al Quran yang diturunkan-Nya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmu-Nya; dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi (pula). cukuplah Allah yang mengakuinyaDan ayat Q.S. al-Fushilat (41:47)
...( ((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( (((( ((((((((((( ( ... ((((
Terjemahnya:
... dan tidak ada buah-buahan keluar dari kelopaknya dan tidak seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya...
Abu Hasan al-Asyari berkata: Allah mengetahui dengan pengetahuan, kuasa dengan kekuasaannya, hidup dengan kehidupannya, berkehendak dengan kehendaknya, berbicara dengan perkataannya, mendengar dengan pendengarannya, melihat dengan penglihatannya.
Bagi Muktazilah, sifat sama dengan Zat. Sifat tidak mempunyai pengertian yang sebenarnya. Jika dikatakan, yang mengetahui ('Alim), maka artinya menetapkan pengetahuan ('Ilm) bagi Allah, dan yang mengetahui itu adalah Zat-Nya sendiri. Dalam hal ini, menetapkan sifat hanya sekedar untuk memahami bahwa Allah bukanlah jahil. Seperti juga mengatakan yang berkuasa (qadir) adalah menetapkan kekuasaan (qudrah) bagi Allah. Kekuasaan itu adalah Zat-Nya sendiri. Artinya, menafsirkan kelemahan Allah.
Masih berbicara tentang tauhid, pemikiran al-Asy'ari yang lain ialah, bahwa Tuhan dapat dilihat di akhirat. Untuk itu, al-Asy'ari membawakan argumen rasio dan nash.Yang tidak dapat dilihat, kata al-Asy'ari, hanyalah yang tak punya wujud. Setiap wujud mesti dapat dilihat, Tuhan berwujud, dan oleh karena itu dapat dilihat. Argumen al-Qur'an yang dimajukannya antara lain, "Wajah-wajah yang ketika itu berseri-seri memandang kepada Allah" (QS. al-Qiyamah: 22-23). Menurut al-Asy'ari kata nazhirah dalam ayat itu tak bisa berarti memikirkan seperti pendapat Muktazilah, karena akhirat bukanlah tempat berfikir; juga tak bisa berarti menunggu, karena wajah atau muka tidak dapat menunggu, yang menunggu adalah manusia. Lagi pula, di surga tidak ada penungguan, karena menunggu mengandung arti dan membuat kejengkelan dan kebosanan. Oleh karena itu, nazhirah mesti berarti melihat dengan mata kepala.
Sungguhpun al-Asy'ari berpendapat, bahwa orang-orang mukmin nanti dapat melihat Tuhan di Akhirat dengan mata kepala, namun pemahamannya bukanlah bersifat harfiyah. Tetapi menghendaki suatu penafsiran lagi yaitu, bahwa melihat Tuhan itu tidak mesti mempunyai tempat dan terarah pada tujuan, tetapi hanya merupakan suatu penglihatan pengetahuan dan kesadaran, dengan mempergunakan mata, yang belum terfikirkan bagi kita sekarang, bagaimana bentuk mata itu nantinya. Namun demikian, untuk dapat menerima, bahwa Tuhan dapat dilihat nanti diakhirat, maka al-Asy'ari memerlukan pula untuk menafsirkan atau mentakwilkan ayat yang berikut ini: Artinya:"Penglihatan tak dapat menangkap-Nya tetapi ia dapat mengangkat penglihatannya."(al-An'am: 103). Ayat tersebut di atas diartikan oleh al-Asy'ari, bahwa yang dimaksud tidak dapat melihat Tuhan adalah di dunia ini, dan bukan di akhirat. Dan juga diartikan tidak dapat melihat Tuhan di akhirat bagi orang kafir.
Al-Asy'ari, seperti Muktazilah, meyakini bahwa Allah adalah Maha Adil. Tetapi seperti kaum Salafi, ia menolak bahwa kita mewajibkan sesuatu kepada Allah. Dan juga menolak faham al-Shalah wa al-Ashlah Muktazilah, artinya, Tuhan wajib mewujudkan yang baik, bahkan yang terbaik untuk kemaslahatan manusia. Allah, kata al-Asy'ari, bebas memperbuat apa yang kehendaki-Nya.
Al-Asy'ari meninjau keadilan Tuhan dari sudut kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Keadilan diartikannya "menempatkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya,"yaitu seseorang mempunyai kekuasaan mutlak atas harta yang dimilikinya serta mempergunakannya sesuai dengan pengetahuan pemilik. Tidak dapat dikatakan salah, kata al-Asy'ari, kalau Tuhan memasukkan seluruh umat manusia ke dalam sorga, termasuk orang-orang kafir, dan juga tidak dapat dikatakan Tuhan bersifat dzalim, jika Ia memasukkan seluruh manusia ke dalam neraka. Karena perbuatan salah dan tidak adil menurut pendapatnya adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan karena diatas Tuhan tidak ada undang-undang atau hukum, maka perbuatan Tuhan tidak pernah bertentangan dengan hukum.
Oleh karena itu, Tuhan sebagai pemilik yang berkuasa mutlak, dapat berbuat apa saja yang dikehendaki-Nya terhadap makhluk-Nya. Jika Tuhan menyakiti anak-anak kecil di hari kiamat, menjatuhkan hukuman bagi orang mukmim, atau memasukkan orang kafir kedalam surga, maka Tuhan tidaklah berbuat salah dan dzalim. Tuhan masih tetap bersifat adil. Upah yang diberikan Tuhan hanyalah merupakan rahmat dan hukuman tetap merupakan keadilan Tuhan.
Karena manusia, bagi al-Asy'ari, selalu digambarkan sebagai seorang yang lemah, tidak mempunyai daya dan kekuatan apa-apa disaat berhadapan dengan kekuasaan absolut mutlak. Karena manusia dipandang lemah, maka paham al-Asy'ari dalam hal ini lebih dekat kepada faham Jabariyah (fatalisme) dari faham Qadariyah (Free Will). Manusia dalam kelemahannya banyak tergantung kepada kehendak dan kekuasaan Tuhan. Untuk menggambarkan hubungan perbuatan dengan kemauan dan kekuasaan mutlak Tuhan al-Asyari memakai istilah al-kasb (acquisition, perolehan). Al-Kasb dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang timbul dari manusia dengan perantaraan daya yang diciptakan oleh Allah. Tentang faham kasb ini, al-Asy'ari memberi penjelasan yang sulit ditangkap. Disatu pihak ia ingin melukiskan peran manusia dalam perbuatannya. Namun dalam penjelasannya tertangkap bahwa kasb itu pada hakekatnya adalah ciptaan Tuhan. Jadi, dalam teori kasb manusia tidak mempunyai pengaruh efektif dalam perbuatannya. Kasb, kata al-Asy'ari, adalah sesuatu yang timbul dari yang berbuat (al-muhtasib) dengan perantaraan daya yang diciptakan.
Melihat kepada pengertian,"sesuatu yang timbul dari yang berbuat" mengandung atas perbuatannya. Tetapi keterangan bahwa "kasb itu adalah ciptaan Tuhan" menghilangkan arti keaktifan itu, sehingga akhirnya manusia bersifat pasif dalam perbuatan-perbuatannya. Argumen yang dimajukan oleh al-Asy'ari tentang diciptakannya kasb oleh Tuhan adalah ayat: "Allah menciptakan kamu dan perbuatan-perbuatan kamu."(QS.al-Shaffat 37:96)
Jadi dalam paham al-Asy'ari, perbuatan-perbuatan manusia adalah diciptakan Tuhan. Dan tidak ada pembuat(agen) bagi kasb kecuali Allah. Dengan perkataan lain, yang mewujudkan kasb atau perbuatan manusia, menurut al-Asy'ari, sebenarnya adalah Tuhan sendiri.
Bahwa perbuatan manusia sebenarnya adalah perbuatan Tuhan, dapat dilihat dari pendapat al-Asy'ari tentang kehendak dan daya yang menyebabkan perbuatan menjadi wujud. Al-Asy'ari menegaskan bahwa Tuhan menghendaki segala apa yang mungkin dikehendaki. Tidak satupun didalam ini terwujud lepas dari kekuasaan dan kehendak Tuhan. Jika Tuhan menghendaki sesuatu, ia pasti ada, dan jika Tuhan tidak menghendakinya niscaya ia tiada. Firman Tuhan: "Kamu tidak menghendaki kecuali Allah menghendaki" QS. al-Insan 76:30). Ayat ini diartikan oleh al-Asy'ari bahwa manusia tak bias menghendaki sesuatu, kecuali jika Allah menghendaki manusia supaya menghendaki sesuatu itu. Ini mengandung arti bahwa kehendak manusia adalah satu dengan kehendak Tuhan, dan kehendak yang ada dalam diri manusia, sebenarnya tidak lain dari kehendak Tuhan.
Dalam teori kasb, untuk terwujudnya suatu perbuatan dalam perbuatan manusia, terdapat dua perbuatan,yaitu perbuatan Tuhan dan perbuatah manusia. Perbuatan Tuhan adalah hakiki dan perbuatan manusia adalah majazi (sebagai lambang). Al-Baghdadi mencoba menjelaskan kepada kita sebagai berikut. Tuhan dan manusia dalam suatu perbuatan adalah seperti dua orang yang mengangkat batu besar; yang seorang mampu mengangkatnya sendirian, sedangkan yang seorang lagi tidak mampu. Kalau kedua orang tersebut sama-sama mengangkat batu besar itu, maka terangkatnya batu itu adalah oleh yang kuat tadi,namun tidak berarti bahwa orang yang tidak sanggup itu tidak turut mengangkat. Demikian pulalah perbuatan manusia. Perbuatan pada hakekatnya terjadi dengan perantaraannya daya Tuhan, tetapi manusia dalam pada itu tidak kehilangan sifat sebagai pembuat. C. Tokoh-tokoh penting al-Asyariyah.
Seperti yang terjadi pada kebanyakan ideologi atau struktur pemikiran yang berusaha untuk tampil koheren, Asyariyah sebagai suatu paham tidak luput dari upaya revisi dan rekonstruksi para pendukungnya. Dengan menawan, pesona yang mungkin saja naf, al-Asyari telah membentuk dan melengkapi sebisanya sebuah bangunan besar teologi namun bangunan besar tersebut tidak sepi dari kritik.Meski harus diingat, bahwa al-Asyari tetap memainkan peranan referensial yang vital bagi siapapun yang ingin mengetahui paham Asyariyah. Berikut tiga nama besar pengikut paham Asyariyah;1. Al-Baqillani.
Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Thayyib ibnu Muhammad Abu Bakar al-Baqillani, lahir di Bashrah tahun 338H/950 M, dan wafat tahun 403 H/1013 M. Dalam usia 63 tahun. Al-Baqillani sebagai sebagai tokoh teologi dalam Islam mempunyai wawasan keilmuan di bidang ini cukup mendalam dan sejalan dengan konsep aliran Asyariyah. Meski menjadi salah satu eksponen Asyariyah terpenting, al-Baqillani dianggap berbeda pendapat dengan al-Asyari pada beberapa hal.
Pertama, mengenai sifat Tuhan, tidak seperti al-Asyari, al-Baqillani menganggap bahwa apa yang kita anggap sebagai sifat Allah bukanlah sifat tetapi modus (hal), akan tetapi pengertian modus al-Asyari ditolak oleh al-Baqillani. Ia berkeyakinan bahwa, mengetahui bagi Tuhan bukanlah melalui sifat dan bukan pula dengan zat. Apabila Tuhan mengetahui dengan sifat-Nya, maka berarti Tuhan bergantung pada sifat dan segala kemampuan sifat. Jikalau Tuhan mengetahui melalui zat-Nya, maka sudah barang tentu zat-Nya terbagi-bagi, dalam hal itu tidak mungkin terjadi. Jika al-Asyari menganggap bahwa sifat-sifat Allah adalah modus di mana setiap kata yang menggambarkan sifat tersebut hanya merefleksikan satu makna dalam pikiran, bagi al-Baqillani sifat-sifat tersebut adalah entitas-entitas yang ada dalam Zat Tuhan, bukan modus.
Kedua, tentang perbuatan manusia, tidak seperti al asyari yang dengan teori kasb-nya berhasil mempertahankan kehendak mutlak Allah atas ciptaan, al-Baqillani memiliki sejenis revisi terhadap teori kasb gurunya. Menurut al-Baqillani ada perbuatan yang terjadi berdasarkan pilihan manusia dan ada perbuatan yang manusia terpaksa melakukannnya. Pada perbuatan yang manusia memiliki kemerdekaan melakukannya, kemerdekaan tersebut tidak bisa di maknai sebagaimana kaum Muktazilah memaknai kemerdekaan. Manusia hanya mampu berbuat dengan qudrah atau daya yang di ciptakan padanya. Manusia hanya mampu berbuat ketika terjadi perbuatan, sebab ia tidak diberi daya sebelumnya.
Menurut al-Baqillani, Allah memberikan daya untuk berbuat kepada manusia yang sebelumnya belum ada. Daya itu ada, bersamaan dengan terlaksananya perbuatan, sebagaimana cincin bergerak bersamaan dengan gerakan tangan. Air memancar bersamaan dengan terceburnya batu kedalam suatu bejana. Seseorang mengetahui rasa sakit bersamaan dengan adanya sakit. Al-Baqillani mengutip ayat-ayat Alquran untuk menegaskan tidak adanya daya sebelum perbuatan, misalnya;( ( ((( (((((((((((((((((((((( (((( (((((((( (( Terjemahnya:
Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((((
Terjemahnya:
dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin.
.
2. Imam al-Haramain Abd al-Malik al-Juwaini
Nama lengkapnya ialah Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Juwaini an-Nisaburi, lahir di Bustanikan, Nisabur 18 Muharam 419/12 Februari 1028 dan wafat 23 Rabiul Akhir 475/20 Agustus 1085 yang terkenal dengan julukan Imam Haramain. Ahli fikih, ahli ushul fikih, dan ahli ilmu kalam(teologi), guru besar di Madrasah Nizamiyah.
Al-Juwaini juga tidak menerima mentah-mentah ajaran al-Asyari. Setidaknya ada dua poin revisi al-Juwaini terhadap al-Asy`ari; pertama, tentang antromorphisme (penyerupaan Tuhan dan manusia) di mana al-Juwaini, tidak seperti al-Asyari, membolehkan tawil atas ayat-ayat antropormorphis, seperti istawa ditakwilkan menguasai, tangan Tuhan mesti ditakwilkan kekuasaan Tuhan, mata Tuhan sebagai penjagaan/pengawasan Tuhan, dan wajah Tuhan sebagai wujud Tuhan. Kedua, al-Juwaini berpaling jauh dari teori kasb al-Asyari tentang perbuatan manusia, suatu kenyataan yang teramati dengan baik sebagai ekses Muktazilah. Sebagaimana pandangan al-Asyari bahwa perbuatan manusia sepenuhnya adalah perbuatan Tuhan dengan jalan manusia memperoleh perbuatannya dari Tuhan. Bagi al-Juwaini adalah tidak logis mempertahankan kekuasaan (pada manusia) yang tidak memiliki efek sama sekali, ini sama saja dengan menolak kekuasaan tersebut semuanya. Perbuatan manusia, menurut al-Juwaini mestilah dipandang berasal dari kekuasaannnya sendiri dalam pengertiannya yang hakiki, meskipun manusia tidak mewujudkan dan menciptakan perbuatannya. Alasannya sangat etimologis, penciptaan adalah tindak kemandirian yang mengadakan sesuatu dari ketiadaan, sedangkan manusia tidaklah mandiri meskipun ia merasakan kekuasaaan dan daya dalam dirinya.
Asas epistemologis teori Kasb al-Juwaini adalah prinsip kausalitas. Akibat diciptakan oleh suatu sebab, yang pada gilirannya sebab tersebut diciptakan oleh sebab yang lain, begitu seterusnya hingga rantai sebab akibat tersebut berhenti pada Sebab Hakiki, Allah swt.
3. Abu Hamid Al-Gazali
Lahir di Tus, Khurasan 450-505H/1058 - 19 Desember 1111 M, memperoleh kemasyuran sebagai pengikut sekaligus sebagai pengembang ajaran-ajaran Asyariah. Banyak peneliti yang menetapkan bahwa al-Ghazali-lah yang memantapkan posisi paham Asyariyah di kalangan ummat Islam Sunni hingga hari ini.
Jika ditilik, menurut para peneliti ajaran-ajaran Asyariah, al-Ghazali, tidak seperti al-Baqillani dan al-Juwaini, tidak berbeda dengan al-Asyari. Al-Gazali mengakui bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat qadim yang tidak identik dengan zat-Nya. Ia juga berpendapat bahwa Al-Quran qadim dan tidak diciptakan. Tentang perbuatan manusia, menurut al-Ghazali, Tuhan-lah yang menciptakan perbuatan tersebut, juga al-Ghazali berkeyakinan bahwa wujud Tuhan dapat dilihat. Mengenai keadilan Tuhan, al-Ghazali menyandarkan dirinya pada prinsip kemutlakan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan tidak akan memiliki sejenis kewajiban untuk memberi surga kepada orang mukmin dan memasukkan neraka orang-orang kafir.
Al-Ghazali dalam kitabnya Miraj as-Salikin dengan tegas mengatakan bahwa Tuhanlah pencipta perbuatan-perbuatan (mukhtari al-afal). Dialah juga yang mengadakan sebab-sebab yang pertama (mujid al-sabab al-ula) dan akibat-akibat dari sebab-sebab itu (al-musabbabat), juga adalah perbuatan-Nya. Dengan demikian, bukan hanya kehendak yang merupakan perbuatan Tuhan, melainkan juga al-qudrah dan perbuatan itu sendiri juga merupakan perbuatan-Nya. Manusia hanyalah tempat berlakunya perbuatan-perbuatan Tuhan. Kendatipun demikian, al-Ghazali tetap membedakan perbuatan yang bersifat ikhtiyari dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya thabii atau idhthirari. Perbuatan yang ikhtiyari senantiasa mempunyai mabda (prinsip), wasath (sarana), dan kamal (tujuan akhir). Prinsipnya adalah untuk mencapai tujuan, mediumnya adalah sikap mencari (al-sulk al-thalabi) dan tujuannya adalah untuk mencapai yang diinginkan.
D. Perkembangan Aliran Asyariah sebagai Aliran Ahlu as-Sunnah wal Jamaah
Seperti telah disebutkan di atas, bahwa dalam faham teologi al-Asy'ari manusia selalu digambarkan sebagai seorang yang lemah, yang tidak mempunyai daya dan kekuatan apa-apa disaat berhadapan dengan kekuasaan yang absolut, apalagi berhadapan dengan kekuasaan mutlak Allah. Teologi ini timbul merupakan refleksi dari status sosial dan kultural masyarakat pada masanya, yaitu keadaan masyarakat Islam pada abad ke-9 M. dimana raja-raja selalu berkuasa dengan diktator dan mempunyai hak penuh untuk menghukum siapa saja yang diinginkannya, sang raja tidak perlu patuh dan tunduk kepada undang-undang dan hukum. Sebab undang-undang dan hukum itu adalah bikinannya sendiri.
Karena teologi al-Asy'ari didirikan atas kerangka landasan yang menganggap bahwa akal manusia mempunyai daya yang lemah, maka disinilah letak kekuatan teologi itu, yaitu ia dengan mudah dapat diterima oleh umumnya umat Islam yang bersifat sederhana dalam pemikiran. Kunci keberhasilan teologi al-Asy'ari ialah karena sejak awal berdirinya ia telah berpihak kepada awwamnya-umat Islam, yang jumlahnya selalu mayoritas di dunia Sunni. Mereka adalah orang-orang yang tidak setuju dengan ajaran-ajaran Mu'tazilah.
Sejarah menunjukkan, bahwa aliran al-Asy'ari telah berhasil menarik rakyat banyak di bawah naungannya berkat campur tangan khalifah al-Mutawakkil, ketika yang terakhir ini membatalkan aliran Muktazilah sebagai paham resmi pada waktu itu. Kemudian setelah wafatnya al-Asy'ari pada tahun 935 M. Ajarannya dikembangkan oleh para pengikutnya, antara lain, al-Baqillani, al-Juwaini dan al-Ghazali. Akhirnya, aliran itu mengalami kemajuan besar sekali, sehingga mayoritas umat Islam menganutnya sampai detik ini.
Adalah berkat kepiawaian dan kerja keras dari seorang al-Ghazali-lah, maka paham Asyariah sebagai paham teologi diterima oleh kebanyakan masyarakat Muslim Sunni. Al-Ghazali mampu memikat hati Muslim Sunni dikarenakan karena beberapa alasan, pertama, alasan penamaan. Sejak awal sejarahnya, Asyariah diproklamirkan oleh pendukungnya dengan sebutan lain, seperti pendukung Ahl al-Hadist dan Ahl as-Sunnah, dua sebutan yang menggetarkan hati kaum muslim yang tak pernah sekejap pun berhenti merindukan Nabi Suci saw. Kata-kata seperti sunnah, hadis dan semacamnya, secara langsung membawa efek kerinduan kepada Nabi Suci saw. sehingga efek tak sadar dari kuasa bahasa langsung termanifestasi, meski sifatnya banal dan anti kritik.
Kedua, kemampuan al-Ghazali menampilkan gagasan-gagasan Asyariah dalam bahasa-bahasa awam yang sepi dari terminologi filosofis yang jauh dari jangkauan keterpahaman masyarakat awam. Dengan demikian, gagasan-gagasan Asyariah ala al-Ghazali begitu mudah dikenal dan digeluti.
Ketiga, al-Ghazali begitu toleran terhadap pendekatan-pendekatan beragama yang lain, kemampuannya untuk mengkombinasikan fikih dan tasawuf begitu melegenda, sehingga secara akademis, ditangannyalah dimulai dialog antar dua tradisi yang sering salah paham satu sama lain. Hasrat al-Ghazali dalam mengadopsi metode inklusif dalam menghampiri agama membuatnya sangat dekat dengan berbagai kalangan sehingga aktifitas-aktifitasnya yang bermuatan Asyariah bisa terus berkembang.
Namun analisis lain bisa ditampilkan. Sebenarnya keberhasilan Asyariah mendominasi panggung teologi Sunni tidak pernah bisa dijelaskan tanpa menghubungkannya dengan dinamika kekuasaan poitik yang terjadi pada zaman al-Ghazali. Setelah sempat pudar pesonanya karena aktifitas politik al- Mutawakkil, paham Mutazilah kembali naik panggung setelah Baghdad diinvasi oleh Dinasti Buwaihi di bawah Ahmad bin Buwaihi yang beraliran Syiah pada tahun 1055 M. Pada masa Dinasti Buwaihi inilah penganut-penganut papan atas pengikut Muktazilah kembali menduduki posisi penting di kesultanan sehingga hampir otomatis aktifitas-aktifitas penganut Asyariah tertekan hingga Dinasti Buwaihi digulingkan oleh Tughril dari Dinasti Saljuk pada 1055 M, bahkan Abu Nasr Muhammad bin Mansyur Al Kunduri (w. 456 H) wazir Tughril melakukan perburuan terhadap pemuka dan penganut paham Asyariah. Keadaan ini berhenti ketika Tughril wafat pada 1063 M dan digantikan oleh Alp Arselen yang memilih Nizam al-Mulk sebagai wazirnya. Al-Mulk yang beraliran Asyariah mulai mengkonsolidasikan paham Asyariah dengan mendirikan sekolah-sekolah al-Nizamiah, di mana pada salah satu al-Nizamiah itulah al-Ghazali mengajarkan paham Asyariah.
Mundurnya Muktazilah dan naik panggungnya kembali Asyariah, tidak saja terjadi di Baghdad, Syam dan daerah kekuasaan Saljuk. Di Mesir, Asyariah di bawa masuk oleh Salah al-Din al-Ayubi, ke Maroko dan Andalusia oleh Muhammad ibnu Tumart, murid al-Ghazali sekaligus pendiri dinasti Muwahhid. Ke India dan bagian timur dunia Islam oleh Mahmud al-Gaznawi.
Di dunia Sunni, barulah pada abad ke-19 M, teologi rasional moderat yang berakar kuat pada tradisi falsafah dan hikmah mulai muncul kembali. Tradisi ini adalah respon intelektual-spiritual terhadap kondisi ummat yang bodoh, miskin, terbelakang serta terkolonisasi oleh Eropa dan Rusia. Keadaan inilah yang mendorong sejumlah tokoh seperti Syah Wali Allah, al-Afgani dan Muhammad Abduh untuk bangkit dengan arus pikiran yang lebih segar dan dinamis ketimbang apa-apa yang disediakan oleh paham Asyariah selama ini.
E. Pengaruh Aliran Asyariah di Dunia Islam
Sebuah kajian atau kritikan terhadap teologi yang berkembang bukanlah usaha untuk menghilangkan subtansi atau membongkar total terhadap pemikiran-pemikiran yang sudah dibangun oleh para teologi yang berkembang di zamannya, namun untuk melihat kembali apakan pemikiran tersebut masih relevan dikembangkan pada zaman sekarang yang penuh dengan berbagai macam karakteristik dan dinamika pemikiran atau pemikiran tersebut perlu dikonstruksi sehingga mampu berdaptasi dengan kehidupan modern, disamping itu dapat mengkomparasikan antara beberapa pemikiran para teolog yang berbeda dalam metodologi objektifitas dan kemampuan dalam memahami kebenaran/hakekat.
Jika disebut paham Asyari, kita maksudkan keseluruhan penjabaran simpul (aqidah) atau simpul-simpul (aqaid) kepercayaan Islam dalam Ilmu Kalam yang bertitik tolak dari rintisan seorang tokoh besar pemikir Islam, Abu Hasan Ali al-Asyari. Penalaran Asyari disebut ortodoks karena lebih setia kepada sumber-sumber Islam sendiri seperti Kitab Allah dan Sunnah Nabi daripada penalaran kaum Muktazilah dan para Failasuf. Meskipun mereka ini semuanya, dalam analisa terakhir, harus dipandang secara sebenarnya tetap dalam lingkaran Islam, namun, dalam pengembangan argumen-argumen bagi paham yang mereka bangun, mereka sangat banyak menggunakan bahan-bahan falsafah Yunani.
Tetapi penggunaan argumen-argumen logis dan dialektis tidak terbatas hanya kepada kaum Muktazilah dan para Failasuf saja. Kaum Asyari juga banyak menggunakannya, meskipun metode tawil yang menjadi salah satu akibat penggunaan itu hanya menduduki tempat sekunder dalam sistem Asyari. Ini terutama sejak tampilnya Imam al-Ghazali sekitar dua abad setelah al-Asyari, yang dengan kekuatan argumennya yang luar biasa, disertai contoh kehidupan yang penuh zuhud, mengembangkan paham Asyari menjadi standar paham ortodoks atau Sunni dalam aqidah.
Disamping menuturkan aqidah Ahl al-Sunnah yang kemudian ia nyatakan sebagai ia ikuti sendiri itu, al-Asyari, seperti telah disinggung di depan, juga mengembangkan alur argument logis dan dialektisnya sebagaimana is pelajari dari guru Muktazilah. Dan pengembangannya oleh Asyari, yang kemudian lebih dikembangkan lagi oleh para pengikutnya, terutama al-Ghazali, menjadi tumpuan kekuatan paham Asyari itu sebagai doktrin dalam aqidah Islamiah kaum Sunni. Ilmu Kalam seperti yang dipelopori oleh Asyari dan dikembangkan oleh al-Ghazali itu telah mempengaruhi banyak agama di dunia, khususnya yang bersentuhan langsung dengan Islam, yaitu Yahudi dan Kristen, sebegitu rupa. Sehingga banyak pemikir Yahudi sendiri memandang bahwa agama Yahudi seperti yang ada sekarang ini adalah agama Yahudi yang dalam bidang teologi telah mengalami pengislaman, seperti tercermin dalam pembahasan buku Austryn Wolfson, Repurcussion of Kalam in Jewish Philosophy (Pengaruh Kalam dalam Falsafah Yahudi).
Sekarang ini, di zaman modern, para pengikut paham Asyari boleh merasa lebih mantap dan berbesar hati, sebab, sepanjang pembahasan William Craigh, seorang ahli filsafat modern dari Berkeley, California, ilmu pengetahuan mutakhir, khususnya teori-teori tentang asal kejadian alam raya seperti teori ledakan besar dalam Astronomi modern, sangat menunjang argumen-argumen Ilmu Kalam, khususnya dalam pandangan bahwa alam raya berpermulaan dalam suatu titik waktu di masa lampau, dan bahwa ia diciptakan dari tiada.
Tanpa kehilangan pandangan tentang segi-segi kuat diatas itu, pembicaraan tentang paham Asyari, tidak mungkin lepas dari segi-segi lemahnya, baik dalam pandangan para pemikir Islam sendiri di luar kubu Kalam Asyari, maupun dari dalam pandangan pemikir lainnya. Dalam batasan ruang dan waktu, kita akan hanya menyinggung satu segi saja yang paling relevan dan juga paling banyak dijadikan sasaran kritik, yaitu pandangan dalam sistem paham Asyari tentang perilaku manusia berkenaan dengan masalah sampai dimana manusia mampu menentukan sendiri kegiatannya dan sampai dimana ia tidak berdaya dalam masalah penentuan kegiatan itu berhadapan dengan qudrat dan iradat Tuhan.
Dari kutipan tentang paham Ahl al-Sunnah yang dijabarkan Asyari, sesungguhnya Asyari bukanlah seorang Jabari sehingga dapat disebut fatalis. Tetapi ia juga bukan seorang Qadari yang berpaham tentang kemampuan penuh manusia menentukan perbuatannya, seperti kaum Muktazilah dan Syiah. Maka tidak heran,Ibn Taymiyyah menganggapnya sebagai salah satu keanehan dan absurditas Ilmu Kalam. Ibn Taymiyyah sendiri, karena menolak baik Qadariyah maupun Jabariyah, juga tampil dengan konsepnya jalan tengah, yaitu, konsep bahwa Allah telah menciptakan dalam diri manusia kehendak (iradah), yang dengan iradah itu manusia mampu memilih jalan hidupnya, baik maupun buruk. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan1. Sejarah kemunculan aliran Asyariah selain merupakan respon intelektual terhadap aliran Mutazilah, ia juga merupakan pisau sekaligus tameng bagi penguasa politik yang mengambil posisi oposisi.
2. Al-Asyari sebagai pendiri mazhab mengkonsolidasikan gagasan-gagasannya dengan jalan menulis buku dan mengajar. Dengan demikian ia telah membangun sebuah tradisi teologi yang masih dominan hingga hari ini.
3. Al-Baqillani, al-Juwaini, dan al-Ghazali adalah tiga nama eksponen utama paham Asyariyah yang sedikit banyak merevisi pandangan-pandangan Sang pendiri mazhab. Di antara ketiganya, al-Ghazali-lah yang menikmati posisi terpandang sebagai eksponen Asyariyah terbesar.
4. Sejarah paham Asyariyah dari awal pembentukannya hingga mencapai kedewasaan konsolidasinya tidak pernah bisa dilepaskan dari sejarah politik kekuasaan yang memberi konteks pada isi doktrin mereka.
5. Meski sebagian peneliti menyayangkan pandangan bahwa Asyariyah berkarakter tradisional dan jumud, padahal seharusnya Asyariyah layak dilabeli gerakan progresif yang ditinjau dari pengembangan teori makna dan bahasa yang menarik, jejak-jejak teologi Asyariah seputar masalah takdir, peran dan kedudukan akal, kedudukan manusia pada hari akhirat dan kehenda Tuhan telah membawa umat pada mentalitas yang kurang sehat.B. Saran dan Implikasi
Diharapkan dengan pembahasan ini, mata kita semakin terbuka dan cerdas dalam melihat segala perbedaan yang merupakan sebuah keniscayaan. Wallahu alam bis-shawwaab.DAFTAR PUSTAKAAbbas, Nukman. Al-Asy`ari,Misteri Perbuatan Manusia dan Takdir Tuhan. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
Al-Asyari, Abu al-Hasan Ali bin Ismail. Al-Ibanah `an Ushul ad-Diyanah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th
____________Kitab al-Luma' Fi al-Rad'ala ahl al-Zaigh wa al-Bida'. Kairo, 1965.____________(Fauqiyah Husein Mahmud, Ed). Al-lbanah 'an Ushul al-Diyanah, Mesir, 1977.
Al-Asyari, Hasan Mahmud. Dirasat Arabiyah wa Islamiyah I. Kairo. Dar el Ulum, 1985.
Al-Baghdadi, Abd al-Qahir. Kitab Ushul al Din. Beirut, 1981.Al-Maghribi, Ali Abdul Fatah. Al-Firaq al-Kalamiyyah al-Islamiyyah. Kairo: Maktabah Wahbah,1995.
Al-Syahrastani, Abi al-Fath Muhammad Abdul Karim ibnu Abi Bakar Ahmad. Al-Milal wa Al-Nihal. Terj. Aswadie Syukur. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006.____________ Al-Milal wa Al-Nihal. Kairo. Muassasah Halbi wa Al-Syirkah li an-Nasyri wa at-Tauzi,1968.Allah, Zuhdi Jar. Al-Mu'tazilah. Beirut, 1974Amin, Ahmad. Zuhr Islam. Cet. III. Kairo: An-Nahdah, 1952.Bishai, Wilson. B. Islamic History of the Middle East. Boston: Harvard Univesity,1968.Gardet, Louis & J. Anawati. Falsafat al-Fikrial-Dini Bain al-Islam wa al-Masihiyah I. Bairut, 1976.
Harahap, Syahrin. Hasan Bakti Nasution. Ensiklopedi Aqidah Islam. Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003.
Kasim, Mahmud. Dirasat Fi al-Falsafah al-Islamiyyah. Mesir, 1973.
Madjid, Nurcholish. Islam Doktrin dan Peradaban. Cet. IV; Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2000.
Madkour, Ibrahim. Fi al-Falsafah al-Islamiyyah II. Mesir, 1976.Musa, Jalal Muhammad Abdul Hamid. Nasyatu al-Asyariyah wa Tathawwuruha. Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani,1970.Nasution, Harun, Teologi Islam. Cet. II; UII Press: Jakarta, 2006
___________, Pembaharuan dalam Islam. Cet. IX; Jakarta: Bulan Bintang. 1992.Program Alquran in Word.Schimmel, Annemarie. Islam Interpretatif. Cet. I; Depok: Inisiasi Press, 2003.
Shihab, Quraish. Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?:Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran. Cet.III; Jakarta :Lentera Hati, 2007.Subhi, A. Mahmud. Fi Ilm al-Kalam II. Iskandiyah, 1982.
Tim Ensiklopedi Islam. Ensiklopedi Islam 2 FAS-KAL. Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 2001.
Zahrah, Imam Muhammad Abu. Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.____________Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah. Kairo, t.th.Zuhdi, Halimi. www.al-fitrah.com. (14 Oktober 2009)Makalah Revisi
AL-ASYARIYAH
Sejarah Timbul, Abu> al-Hasan al-Asyari> dan Pokok-pokok Ajarannya,
Tokoh-tokoh Penting, Perkembangannya Sebagai Aliran Ahlussunnah wal Jamaah dan Pengaruhnya di Dunia Islam
Mata Kuliah Sejarah Pemikiran dalam IslamSemester I Tahun Akademik 2009/2010
Oleh :
MURSIDIN
NIM : 80100209093Dosen / Pemandu :
Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag
Dr. Usman, M.AgPROGRAM PASCASARJANA (S2)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2009M. Quraish Shihab, Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?: Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran (Cet.3; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 27.
Banyak riwayat menunjukkan bahwa tokoh-tokoh para sahabat Nabi saw., seperti Abu Bakar, Umar ibn al-Khaththab, Ali ibnu Ali Thalib, Ibnu Masud, Abdullah bin Umar, Zaid ibn Tsabit r.a. memiliki pandangan yang berbeda dalam sekian masalah. Bacalah, misalnya, Tafsir al-Qurtuby, pasti anda akan menemukan aneka perbedaan itu. Lihat selengkapnya pada karya asy-Syahrastany, al-Milal wa an-Nihal, Takhrij Muhammad Fathullah Badran (Cet.2; al-Anglo al-Mishriyah, t.th), h. 27.
Harun Nasution. Teologi Islam. (Cet. 2; Jakarta: UII Press, 2006), h. 3.
Wilson. B Bishai, Islamic History of the Middle East (Boston: Harvard Univesity, 1968), h. 123.
Nukman Abbas, Al-Asyari: Misteri Perbuatan Manusia dan Takdir Tuhan. (Jakarta: Penerbit Erlangga), h. 4.
Ibid., h. 5.
Annemarie Schimmel, Islam Interpretatif (Cet. 1; Depok: Inisiasi Press, 2003), h. 100.
Nukman Abbas, op. cit., h. 103.
Harun Nasution, op. cit. h. 64.
Imam Muhammad Abu Zahrah, Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), h. 189.
Muhammad Imarah, Tayyarat Al-Fiqr al-Islami (Beirut: Dar Asy-Syuruq, 1991), h. 163.
Abdurrahman Badawi, Mazhab al-Islamiyyin (al-Malayin: Dar Ilm, 1884), h. 497. Lihat juga Jalal Muhammad Abdul Hamid Musa. Nasyatu al-Asyariyah wa Tathawwuruha (Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani, 1970), h. 165.
Abu al-Hasan al-Asy'ari. (Fauqiyah Husein Mahmud, Ed) Al-lbanah 'an Ushul al-Diyanah. (Mesir, 1977), h. 9.
Louis Gardet & J. Anawati. Falsafat al-Fikri al-Dini bain al-Islam wa al-Masihiyah I (terj.) (Beirut, 1976), h. 93.
Ali Abdul Fatah al-Maghribi, Al-Firaq al- Kalamiyyah al-Islamiyyah. (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), h. 268.
Ahmad Amin. Zuhr Islam, juz 2 (Cet. 3; Kairo: Dar al-Misriyah, 1952.. h.52.
Nukman Abbas, op. cit., h. 106.
Jalal Muhammad Abdul Hamid Musa, op. cit., h. 171.
Abu al-Hasan Ali bin Ismail al-Asyari, Al-Ibanah `an Ushul ad-Diyanah. (Beirut. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 3. Ali Abdul Fatah al-Maghribi, op. cit., h. 269.
Nukman Abbas, op. cit., h. 108.
Muhammad bin Abdul Karim Al-Syahrastani, Al-Milal wa Al-Nihal. Diterjemahkan oleh Aswadie Syukur (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006), h. 77.
Zuhdi Jar Allah, Al-Mu'tazilah (Beirut, 1974), h. 102.
Louis Gardet & J. Anawati, op cit., h.94. Lihat juga Jalal Muhammad Abdul Hamid Musa,. op. cit., h. 175.
A. Mahmud Subhi, Fi Ilm al-Kalam II (Iskandiyah, 1982), h.159.
Bahwa manusia harus bertanggung jawab atas kehendak dan perbuatannya sendiri menurut pendapat Mu'tazilah dapat dilihat pada Mahmud Kasim, Dirasat Fi al-Falsafah al-Islamiyah (Mesir,1973), h. 164-165.
Nukman Abbas, op. cit. h. 109. Jalal Muhammad Abdul Hamid Musa, op. cit., h. 186.
Ibid.,
Ibid., h. 110.
Abu al-Hasan al-Asy'ari, Al-Ibanah, op. cit., h.8.
Fauqiyah Husein Mahmud, Ed, Al-lbanah.. op. cit., h. 35.
Hasan Mahmud al-Asy'ari, Dirasat Arabiyah wa Islamiyah I (Kairo. Dar el Ulum. 1985), h. 38.
Al-Asyari,. op. cit., h. 28-29. Lihat juga Imam Muhammad Abu Zahrah, op.cit., h. 190-191.
Ibid., h. 31-33. Uraian lebih lanjut dapat dilihat dalam Nurcholish Madjid. Islam Doktrin dan Peradaban (Cet. 4; Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2000), h. 274-276. dan Imam Muhammad Abu Zahrah. op. cit., h. 190-198.
Nukman Abbas, op. cit., h. 113.
Ibid., h. 114.
Ali Abdul Fatah al-Maghribi, op. cit., h. 274.
Abi al-Fath Muhammad Abdul Karim ibnu Abi Bakar Ahmad Al-Syahrastani, Al-Milal wa Al-Nihal. Juz. I (Kairo: Muassasah Halbi wa Al-Syirkah li an-Nasyri wa at-Tauzi, 1968), h. 94.
Jalal Muhammad Abdul Hamid Musa, op. cit., h. 212.
Ibid.,
Abu al-Hasan al-Asy'ari, Kitab al-Luma' Fi al-Rad'ala ahl al-Zaigh wa al-Bida' (Kairo, 1965), h. 30.
Al-Syahrastani. op. cit., h. 104.
Ibrahim Madkour, Fi al-Falsafah al-Islamiyyah II (Mesir. 1976), h. 50.
Lihat Nurcholish Madjid, op. cit., h. 274-276.
Program Alquran in Word.
Al-Syahrastani, op. cit., h. 95.
Subhi, op. cit., h. 51.
Al-Asy'ari. Al-Ibanah. op. cit., h.17. Lihat juga. Al-Syahrastani. op. cit., h.100.
Al-Asy'ari. Ibid., h. 13.
Al-Syahrastani, op. cit., h. 100.
Al-Asy'ari, Al-Ibanah. op. cit., h. 16.
As-Syahrastani. op. cit., h. 102. 113.
Ibid.,
Abu al-Hasan al-Asy'ari, Kitab al-Luma' . op. cit. h. 30.
Ibid.,
Muhammad Abu Zahrah. op. cit. , h. 205.
Al-Asy'ari. al-Luma'. op. cit., h. 76.
Ibid., h. 72.
Al-Asy'ari, Al-Ibanah. op. cit., h. 51.
Al-Asy'ari, Al-Luma'. op. cit., h. 57.
Abd al-Qahir al-Baghdadi, Kitab Ushul al Din. (Beirut, 1981), h. 133-134.
Syahrin Harahap & Hasan Bakti Nasution, Ensiklopedi Aqidah Islam (Cet. 1; Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 70.
Ibid., h. 71.
Nukman Abbas, op. cit., h. 133.
Ibid., h. 134.
Program Alquran in Word.
Tim Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam 2 FAS-KAL. (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 2001), h. 328.
Syahrin Harahap & Hasan Bakti Nasution, op. cit. h. 204-205.
Ibid.,
Nukman Abbas, op. cit., h. 158.
Tim Ensiklopedi Islam, op. cit. h. 278.
Nukman Abbas, loc. cit., h. 160.
Ibid., h. 161.
Ibid., h. 162.
Mahmud Kasim, op. cit., h. 34.
Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam (Cet. IX; Jakarta. Bulan Bintang. 1992), h. 51-88.
Harun Nasution, Pembaharuan, op. cit., h. 51-88.
Harun Nasution, op. cit., h. 74-75.
Ali Abdul Fatah al-Maghribi, op. cit., h. 271.
Ibid., h. 76.
Annemarie Schimmel, op. cit., h. 167.
Halimi Zuhdi, HYPERLINK "http://www.al-fitrah.com" www.al-fitrah.com. (14 Oktober 2010).
Nurcholish Madjid, op. cit., h. 271.
Nurcholish Madjid, op. cit., h. 271.
Ibid., h. 277.
Ibid., h. 280.
Ibid., h. 280-281.
Ibid., h. 282.
Ibid., h. 283-284.