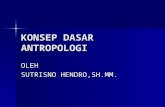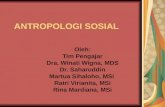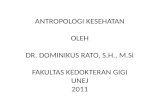Antropologi
-
Upload
tiara-rizky -
Category
Documents
-
view
10 -
download
0
Transcript of Antropologi

Nama : Anggraeni Lailatul Mubarokah
NIM : 1202045098
Kelas : HI Reguler B
Angkatan : 2012
ANTROPOLOGI
Istilah “antropologi” berasal dari bahasa Yunani asal kata “anthropos” berarti
“manusia”, dan “logos” berarti “ilmu”, dengan demikian secara harfiah “antropologi”
berarti ilmu tentang manusia. Para ahli antropologi (antropolog) sering mengemukakan
bahwa antropologi merupakan studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun
generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh
pengertian ataupun pemahaman yang lengkap tentang keanekaragaman manusia
(Haviland, 1999: 7; Koentjaraningrat, 1987: 1-2). Jadi antropologi merupakan ilmu yang
berusaha mencapai pengertian atau pemahaman tentang mahluk manusia dengan
mempelajari aneka warna bentuk fisiknya, masyarakat, dan kebudayaannya.
Antropologi sangat penting di dalam Ilmu Hubungan Internasional yang salah satu
alasannya karena antropologi ini membahas tentang manusia dan kebudayaannya maka
apabila kita telah menjadi salah satu perwakilan negara, kita dapat mengetahui lebih
dalam mengenai negara kita sendiri.
A. Masyarakat
Masyarakat : kumpulan dua org atau lbih yang berinteraksi.
Hakekat dari masyarakat adalah komunikasi.
Ciri masyarakat adanya konflik
terjadinya konflik dikarenakan adanya pemikiran yang berbeda dan adanya perbedaan

kebutuhan antara 1 klmpok dngan klmpok lain.
Perbedaan secara vertikal : - politik : kekuasaan
- ekonomi : miskin dan kaya
Perbedaan secara horizontal : agama, suku dan parpol.
Kompetisi : cikal bakal konflik
Akomodasi : suatu kepentingan yang digabung dan membentuk koalisi.
Asimilasi : penggabungan 2 budaya
2 hal yang termasuk unsur-unsur masyarakat:
- adanya struktur sosial : seperangkat nilai yang dijadikan kerangka atau dasar bagi
masyarakat didalam bertindak atau berperilaku ditempat- tempat yang telah disediakan.
Lapisan sosial merupakan perwujudan dari struktur sosial.
- adanya pranata sosial : seperangakat aturan yang mengatur dan mememaksa orang yang
ada dilingkungannya untuk mematuhi peraturan yang telah ditentukan.
Masyarakat (sebagai terjemahan istilah society) adalah sekelompok orang yang
membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar
interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata
"masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya,
sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas.
Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama
lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang
hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam bermata
pencaharian. Pakar ilmu sosial mengidentifikasikan ada: masyarakat pemburu,
masyarakat pastoral nomadis, masyarakat bercocoktanam, dan masyarakat agrikultural
intensif, yang juga disebut masyarakat peradaban. Sebagian pakar menganggap
masyarakat industri dan pasca-industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari
masyarakat agrikultural tradisional.
Masyarakat dapat pula diorganisasikan berdasarkan struktur politiknya: berdasarkan
urutan kompleksitas dan besar, terdapat masyarakat band, suku, chiefdom, dan
masyarakat negara.
Kata society berasal dari bahasa latin, societas, yang berarti hubungan persahabatan
dengan yang lain. Societas diturunkan dari kata socius yang berarti teman, sehingga arti
society berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata society mengandung
makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam
mencapai tujuan bersama.
B. Budaya/kebudayaan
Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah, yang
merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang
berkaitan dengan budi dan akal manusia.
Ada pula yang mengatakan istilah ”culture” (kebudayaan) berasal dari bahasa Latin
yakni ”cultura” dari kata dasar ”colere” yang berarti ”berkembang tumbuh”. Namun
secara umum pengertian ”kebudayaan” mengacu kepada kumpulan pengetahuan yang
secara sosial yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Makna ini

kontras dengan pengertian ”kebudayaan” sehari-hari yang hanya merujuk kepada bagian-
bagian tertentu warisan sosial, yakni tradisi sopan santun dan kesenian (D’Andrade,
2000: 1999).
Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah
kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak
unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas,
pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian
tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya
diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang
yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa
budaya itu dipelajari.
Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan
luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-
budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.
Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan
adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau
gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari,
kebudayaan itu bersifat abstrak.
Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh
manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang
bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial,

religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam
melangsungkan kehidupan bermasyarakat.
Unsur-unsur kebudayaan
Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur
kebudayaan, antara lain sebagai berikut:
1. Melville J. Herskovits menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu:
o alat-alat teknologi
o sistem ekonomi
o keluarga
o kekuasaan politik
2. Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi:
o sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antara para anggota
masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya
o organisasi ekonomi
o alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan
(keluarga adalah lembaga pendidikan utama)
o organisasi kekuatan (politik)
Wujud kebudayaan
Menurut J.J. Hoenigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga: gagasan, aktivitas,
dan artefak.

Gagasan (Wujud ideal)
Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide,
gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya
abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam
kepala-kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut
menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari
kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para
penulis warga masyarakat tersebut.
Aktivitas (tindakan)
Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia
dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem
sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi,
mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola
tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam
kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati dan didokumentasikan.
Artefak (karya)
Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas,
perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau
hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret
di antara ketiga wujud kebudayaan. Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat,
antara wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan

yang lain. Sebagai contoh: wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah
kepada tindakan (aktivitas) dan karya (artefak) manusia.
Komponen kebudayaan
Berdasarkan wujudnya tersebut, Budaya memiliki beberapa elemen atau komponen,
menurut ahli antropologi Cateora, yaitu :
Kebudayaan material
Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata,
konkret. Termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang
dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi: mangkuk tanah liat, perhisalan,
senjata, dan seterusnya. Kebudayaan material juga mencakup barang-barang,
seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, gedung pencakar
langit, dan mesin cuci.
Kebudayaan nonmaterial
Kebudayaan nonmaterial adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari
generasi ke generasi, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian
tradisional.
Lembaga sosial
Lembaga sosial dan pendidikan memberikan peran yang banyak dalam kontek
berhubungan dan berkomunikasi di alam masyarakat. Sistem sosial yang
terbantuk dalam suatu Negara akan menjadi dasar dan konsep yang berlaku pada
tatanan sosial masyarakat. Contoh Di Indonesia pada kota dan desa dibeberapa

wilayah, wanita tidak perlu sekolah yang tinggi apalagi bekerja pada satu instansi
atau perusahaan. Tetapi di kota – kota besar hal tersebut terbalik, wajar seorang
wanita memilik karier
Sistem kepercayaan
Bagaimana masyarakat mengembangkan dan membangun system kepercayaan
atau keyakinan terhadap sesuatu, hal ini akan mempengaruhi system penilaian
yang ada dalam masyarakat. Sistem keyakinan ini akan mempengaruhi dalam
kebiasaan, bagaimana memandang hidup dan kehidupan, cara mereka
berkonsumsi, sampai dengan cara bagaimana berkomunikasi.
Estetika
Berhubungan dengan seni dan kesenian, music, cerita, dongeng, hikayat, drama
dan tari –tarian, yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Seperti di
Indonesia setiap masyarakatnya memiliki nilai estetika sendiri. Nilai estetika ini
perlu dipahami dalam segala peran, agar pesan yang akan kita sampaikan dapat
mencapai tujuan dan efektif. Misalkan di beberapa wilayah dan bersifat kedaerah,
setiap akan membangu bagunan jenis apa saj harus meletakan janur kuning dan
buah – buahan, sebagai symbol yang arti disetiap derah berbeda. Tetapi di kota
besar seperti Jakarta jarang mungkin tidak terlihat masyarakatnya menggunakan
cara tersebut.
Bahasa
Bahasa merupakan alat pengatar dalam berkomunikasi, bahasa untuk setiap
walayah, bagian dan Negara memiliki perbedaan yang sangat komplek. Dalam
ilmu komunikasi bahasa merupakan komponen komunikasi yang sulit dipahami.

Bahasa memiliki sidat unik dan komplek, yang hanya dapat dimengerti oleh
pengguna bahasa tersebu. Jadi keunikan dan kekomplekan bahasa ini harus
dipelajari dan dipahami agar komunikasi lebih baik dan efektif dengan
memperoleh nilai empati dan simpati dari orang lain.
C. Perubahan sosial budaya
Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola
budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang
terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan
hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Hirschman
mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan.
Perubahan sosial budaya terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya komunikasi;
cara dan pola pikir masyarakat; faktor internal lain seperti perubahan jumlah penduduk,
penemuan baru, terjadinya konflik atau revolusi; dan faktor eksternal seperti bencana
alam dan perubahan iklim, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain.
Ada pula beberapa faktor yang menghambat terjadinya perubahan, misalnya kurang
intensifnya hubungan komunikasi dengan masyarakat lain; perkembangan IPTEK yang
lambat; sifat masyarakat yang sangat tradisional; ada kepentingan-kepentingan yang
tertanam dengan kuat dalam masyarakat; prasangka negatif terhadap hal-hal yang baru;
rasa takut jika terjadi kegoyahan pada masyarakat bila terjadi perubahan; hambatan
ideologis; dan pengaruh adat atau kebiasaan.

Pada dasarnya perubahan sosial dan perubahan budaya itu berbeda, namun memiliki
keterkaitan. Suatu perubahan sosial pasti berpengaruh pada perubahan budaya, sementara
budaya tidak mungkin lepas dari kehidupan sosial masyarakat. Karena itu sering disebut
perubahan sosial budaya untuk mencakup kedua perubahan tersebut.
Perubahan sosial dan budaya memiliki satu aspek yang sama, yaitu kedua-duanya
menyangkut perbaikan dan penerimaan cara-cara baru bagi masyarakat dalam memenuhi
kebutuhannya. Perubahan sosial dan perubahan budaya meski memiliki keterkaitan yang
erat, namun dapat kita jumpai perbedaannya jika dilihat dari arahnya:
Perubahan sosial merupakan perubahan dari segi struktur sosial dan hubungan
sosial masyarakat.
Perubahan budaya merupakan perubahan dalam segi budaya masyarakat.
Adapun perbedaannya dilihat dari segi yang dipengaruhi:
Perubahan sosial terjadi dalam segi pendidikan, tingkat kelahiran penduduk, dan
distribusi kelompok umur.
Perubahan budaya terjadi pada bentuk kesenian, kesetaraan gender, konsep nilai
susila dan moralitas, penemuan baru, dan penyebaran masyarakat. Perubahan
kebudayaan ini jauh lebih luas dari perubahan sosial karena meliputi banyak
aspek, seperti kesenian, iptek, aturan hidup, dan lain-lain.
Perubahan sosial biasanya memiliki beberapa ciri, di antaranya seperti yang diungkapkan
oleh Moore yaitu:

Tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti, karena masyarakat akan
mengalami perubahan (cepat atau lambat) dan berlaku secara tetap.
Perubahan-perubahan itu tidak bersifat sementara maupun terpisah karena
perubahan terjadi secara berurutan.
Perubahan sosial memiliki asas ganda.
Inovasi dan isu-isu akan mempengaruhi perubahan sosial.
Perubahan sosial akan memberi akibat yang lebih luas pada pengalaman individu.
Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial dan Budaya
Perubahan Evolusi dan Revolusi
Perubahan evolusi adalah perubahan-perubahan yang berlangsung lama. Biasanya terjadi
karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan
kondisi baru yang muncul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Contohnya adalah
pada perkembangan ilmu pengetahuan.
Perubahan revolusi adalah perubahan yag berlangsung cepat dan mendasar. Perubahan ini
bisa terjadi karena ada rencana sebelumnya atau tidak sama sekali. Contoh revolusi
adalah revolusi industri di Inggris, dimana terjadi perubahan produksi yang awalnya
tanpa mesin menjadi menggunakan mesin.
Menurut para ahli, agar perubahan revolusi bisa terjadi, maka ada syarat yang harus
dipenuhi, yaitu:
Ada keinginan umum untuk mengadakan perubahan.

Ada pemimpin yang dianggap mampu memimpin masyarakat, menampung
keinginan masyarakat, dan dapat menunjukkan suatu tujuan yang jelas pada
masyarakat.
Ada keadaan yang tepat dan aktor (pelaku perubahan) yang baik untuk memulai
perubahan.
Perubahan Kecil dan Besar
Perubahan kecil adalah perubahan yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti
pada masyarakat. Contoh: perubahan mode pakaian, mode rambut, dan lain-lain yang
tidak berpengaruh bagi masyarakat secara keseluruhan jika kita tidak mengikutinya.
Perubahan besar adalah perubahan yang membawa pengaruh langsung atau berarti bagi
masyarakat. Contohnya penggunaan komputer dan internet untuk menunjang kerja,
penggunaan traktor bagi petani, dan lain-lain yang membawa perubahan signifikan pada
lembaga-lembaga kemasyarakatan.
Perubahan yang Dikehendaki (Direncanakan) dan Tidak Dikehendaki (Tidak
Direncanakan)
Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yangterjadi karena adanya perencanaan
ataupun perkiraan oleh pihak yang merencanakan perubahan tersebut (agent of change).
Agent of change merupakan pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai
pemimpin satu atau lebih kembaga kemasyarakatan. Contoh perubahan ini adalah
kewajiban masyarakat untuk menanam pohon yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang tidak dikehendaki dan
berlangsung diluar jangkauan masyarakat untuk menahannya, dan biasanya menimbulkan
pertentangan di dalam masyarakat. Contohnya kecenderungan untuk mempersingkat
prosesi pernikahan karena memerlukan biaya besar, meski perubahan ini tidak
dikehendaki tapi masyarakat tidak mampu menghindarinya.
Perubahan Progres dan Regres
Perubahan progres adalah perubahan yang membawa keuntungan bagi masyarakat.
Contoh perkembangan pendidikan masyarakat.
Perubahan regres adalah perubahan yang membawa kemunduran bagi masyarakat di
bidang tertentu. Contoh perubahan pola kehidupan remaja yang mabuk-mabukan.
Faktor-Faktor Penyebab Perubahan Sosial Budaya
Perubahan dari dalam Masyarakat
Perubahan jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk akan menimbulkan
perubahan pada kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu
penduduk yang bertambah akan menyebabkan tempat tinggal yang semula
berpusat di keluarga nesar menjadi terpencar karena faktor pekerjaan. Contoh
perubahan penduduk adalah program transmigrasi dan urbanisasi.
Pemberontakan atau revolusi, yang berpengaruh besar pada lembaga-lembaga
masyarakat dan struktur masyarakat. Sebagai contoh G 30 S/PKI yang berakibat
dilarangnya paham komunis si Indonesia.

Peranan nilai yang diubah. Misalnya program keluarga berencana yang mampu
mengubah pandangan masyarakat untuk mengurangi jumlah kelahiran anak.
Peran tokoh karismatik, karena tokoh ini adalah tokoh yang disegani dan
dihormati di masyarakat, maka masyarakat akan cenderung mengikuti arah tokoh
tersebut. Seperti Ir. Soekarno yang memiliki karisma di masyarakat karena
keahliannya berpidato.
Penemuan baru. Penemuan baru terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
1. Inovasi, yaitu proses proses perubahan sosial budaya yang besar tapi terjadi dalam
waktu singkat.
2. Discovery, yaitu penemuan unsur kebudayaan baru oleh seorang atau beberapa
individu.
3. Invention, yaitu saat ketika masyarakat sudah mengakui, menerima, dan
menerapkan penemuan baru tersebut.
Perubahan dari Luar Masyarakat
Faktor alamiah, jika tempat tinggal masyarakat adalah pantai, maka masyarakat
akan cenderung berprofesi sebagai nelayan. Selain itu jika terjadi bencana alam,
maka masyarakat akan pindah ke daerah lain sehingga masyarakat akan
beradaptasi dengan lingkungan baru tersebut dan melahirkan budaya baru.
Peperangan, yang pasti menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat.

Pengaruh kebudayaan masyarakat lain, ketika dua masyarakat saling berinteraksi.
Interaksi tersebut akan menimbulkan perubahan pola pikir dan selanjutnya bisa
terjadi akulturasi atau asimilasi.
1. Akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan dimana kebudayaan setempat
masih terlihat. Sering dianalogikan dengan rumus A+B=AB, dengan A=
kebudayaan asing dan B=kebudayaan setempat.
2. Asimilasi adalah percampuran dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan
yang baru sama sekali. Dianalogikan dengan rumus A+B=C, dengan
A=kebudayaan asing, B=kebudayaan setempat, dan C=kebudayaan baru.
Dalam proses perubahan sosial budaya akibat interaksi masyarakat sering dijumpai istilah
difusi, yaitu penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari sekelompok masyarakat ke
kelompok masyarakat lain.
Faktor pendorong perubahan Sosial Budaya
Penemuan baru.
Perubahan jumlah penduduk.
Pertentangan/konflik.
Pemberontakan/revolusi.
Keterbukaan masyarakat.
Akulturasi.
Asimilasi.
Sistem pendidikan yang maju.

Keinginan untuk maju dan orientasi ke masa depan.
Sikap menghargai hasil karya seseorang.
Faktor Penghambat Perubahan Sosial Budaya
Sikap masyarakat yang tradisional.
Perkembangan IPTEK yang terhambat.
Adat istiadat dan hambatan ideologis.
Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain.
Rasa takut akan terjadi ketidakseimbangan kebudayaan.
Dalam perubahan sosial budaya dikenal adanya konsekuensi, yaitu hasil dari perubahan
sosial budaya. Konsekuensi terbagi dua yaitu konsekuensi yang fungsional dimana
masyarakat menjadi semakin tenteram, dan konsekuensi yang disfungsional dimana
masyarakat mendapat akibat-akibat yang tidak diharapkan. Disorganisasi adalah
perubahan sosial yang hanya sedikit atau bahkan tidak memberi manfaat bagi
masyarakat.
Dampak perubahan sosial budaya
Dampak positif
Kemajuan IPTEK.
Kebutuhan mudah terpenuhi.
Pola pikir masyarakat mengalami kemajuan.
Dampak negatif

Masyarakat menjadi konsumif.
Keresahan sosial.
Ketidakmerataan pembangunan.
Pudarnya norma-norma masyarakat.
Keadaan masyarakat yang mampu beradaptasi dengan perubahan disebut adjusment,
sedangkan bentuk penyesuaiannya disebut integrasi. Keadaan masyarakat yang tidak
mampu beradaptasi dengan perubahan disebut maladjusment, yang akan menimbulkan
disintegrasi.
Untuk menghindari dampak buruk perubahan sosial budaya, maka harus dilakukan
tindakan preventif (upaya pencegahan) dan represif (upaya penanggulangan dampak
buruk).
Bentuk Perubahan Sosial Masyarakat
1. Berdasarkan sifatnya :
a) Perubahan progresif, yaitu perubahan yang mengarah pada keadaan yang lebih baik
dan menuju pada kemajuan.
b) Perubahan regresif, yaitu perubahan yang mengarah pada keadaan yang lebih buruk
dibandingkan sebelumnya.
2. Berdasarkan kesadarannya :
a) Perubahan disengaja (Intended), yaitu perubahan yang dilakukan secara sadar demi
kemajuan masyarakat.
b) Perubahan tidak disengaja (Unintended), yaitu perubahan yang terjadi secara

kebetulan.
3. Berdasarkan percepatannya :
a) Perubahan secara lambat/evolusi, yaitu perubahan yang terjadi secara pelan-pelan dan
tidak terasa.
b) Perubahan secara cepat/revolusi, yaitu perubahan yang terjadi dalam waktu yang
singkat dalam wujud yang terlihat nyata.
Akibat perubahan sosial budaya
• Berakibat positif maka akan melahirkan kondisi hidup yang integratif
• Membawa pengaruh negatif akan melahirkan kondisi yang disintegrasi seperti
kenakalan remaja, kriminalitas dan pergolakan daerah.
Referensi :
- http://antropolog.wordpress.com/perubahan-sosial-budaya/
- http://arisudev.wordpress.com/2010/11/29/perubahan-sosial-budaya/
- http://id.wikipedia.org/wiki
- http://roedijambi.wordpress.com/2010/02/11/teori-evolusi-dan-difusi-
kebudayaan-analisis-komparatif-terhadap-dua-paradigma-dalam-
antropologi/
- http://www.slideshare.net/primus74/pengertian-kebudayaan-menurut-
ilmu-antropologi

- Ihromi, T.O.2006. Pokok-pokok antropologi budaya.Jakarta.Yayasan Obor
Indonesia.
- Sutardi, Tedi.2007.Antropologi: Mengungkap Keragaman
Budaya.Bandung.PT.Setia Purna Inves.