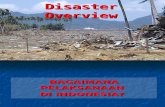4593-6307-1-PB
-
Upload
naroeto-cap-kutil -
Category
Documents
-
view
50 -
download
0
description
Transcript of 4593-6307-1-PB

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Gagal ginjal kronik (GGK) adalah penurunan faal ginjal yang terjadi secara
menahun dan bersifat irreversible, terjadi apabila laju filtrasi glomeruler (LFG)
kurang dari 60 ml/menit/1,73 m2 selama tiga bulan atau lebih, menyebabkan
perubahan struktural dan penurunan jumlah unit fungsional ginjal (nefron) yang
nantinya akan melaju ke arah pemburukan. Penurunan ini cukup berat sehingga
menimbulkan gejala berupa sindroma uremia. Secara fungsional tingkat klirens
kreatinin biasanya dibawah 25 ml/menit, penurunan ini akan terus berlanjut
sampai tingkat klirens kratinin di bawah 10-5 ml/menit, atau kadar kreatinin
serum di atas 10 mg/dl. Keadaan ini disebut gagal ginjal terminal dimana ginjal
tidak dapat menjalankan fungsinya dan akan menimbulkan gejala klinis. Penyebab
gagal ginjal kronis antara lain adalah gangguan imunologis, gangguan metabolik,
gangguan pembuluh darah ginjal, infeksi, gangguan tubular primer, obstruksi
tractus urinarius, kelainan kongenital, dan sebagainya. Gejala klinis baru muncul
bila nefron mencapai kurang dari 70% (Bakri, 2005; Remuzzi et al., 2002).
Penyakit Gagal Ginjal Kronik Terminal (GGKT) sekarang merupakan
masalah kesehatan dunia dengan terjadi peningkatan insidensi, prevalensi serta
tingkat morbiditas, selain itu penyakit ini memerlukan perawatan dengan biaya
perawatan yang mahal dan outcome yang buruk karena penderita GGKT harus
menjalani berulang kali hemodialisis dalam sebulan. Satu kali hemodialisis
membutuhkan biaya berkisar antara 410.000 hingga 680.000. Angka kematian
1

akibat GGKT terus meningkat di banyak negara termasuk di negara berkembang
seperti Indonesia. Menurut US Renal Data System dalam laporan tahunannya
menyebutkan bahwa prevalensi dan insidensi End Stage Renal Disease (ESRD) di
Amerika serikat terus meningkat. Tahun 2000 prevalensi gagal ginjal kronik di
Amerika sebesar 1.311 tiap sejuta penduduk dengan jumlah penderita sebesar 20
juta dan diperkirakan pada tahun 2025 akan mencapai dua kalinya. Insidensi gagal
ginjal kronik di Indonesia diduga sebesar 100-150 tiap 1 juta penduduk per tahun
(Go et al., 2004; Stevens et al., 2006; Kher, 2002; Fatchiati, 2006).
Gagal Ginjal Kronik Terminal (GGKT) tidak saja mengakibatkan kerugian
secara fisik, psikis dan ekonomi pada diri penderita tetapi juga menjadi beban bagi
keluarga, masyarakat, maupun negara. Disamping biaya cuci darah cukup mahal,
kehidupan penderita tergantung dari cuci darah dan cangkok ginjal. Pasien GGKT
aktivitasnya terbatas karena lebih mudah lelah dibanding orang normal,
kebanyakan dari mereka membutuhkan bantuan orang terdekat untuk membantu
aktivitas mereka. Oleh karena itu dukungan dari keluarga dan orang terdekat
sangat berarti bagi pasien GGKT (Bakri, 2005; Remuzzi et al., 2002; Yogiantoro,
2009).
Hemodialisis dianjurkan sedini mungkin untuk menghambat progresivitas
penyakit, yaitu saat pengeluaran kreatinin 9-14 ml/menit/1,73 m2, baik pada
penderita diabetes maupun nondiabetes. Hemodialisis bisa dimulai lebih awal
pada pasien malnutrisi, pasien yang mengalami kelebihan cairan tubuh, penurunan
kesadaran, kejang, radang kandung jantung, hiperkalemia, serta asidosismetabolik
berulang. Hemodiaisis diharapkan mampu menggantikan fungsi ginjal yang rusak
2

sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan diharapkan dapat
memperpanjang usia pasien gagal ginjal kronik terminal. Namun, adanya penyakit
komorbid seperti hepatitis, diabetes melitus, jantung dapat memperburuk kualitas
hidup penderita gagal ginjal. (Markum, 2002; Kunmartini, 2008)
Salah satu penyakit komorbid GGKT adalah hepatitis. Penularannya dapat
melalui proses hemodialisa. Prevalensi kejadian infeksi hepatitis Hepatitis B
Virus (HBV), Hepatitis C Virus (HCV), maupun Hepatitis G Virus (HGV) pada
penderita GGKT dengan hemodialisis adalah yang tertinggi dari infeksi yang lain,
yaitu berkisar antara 3-57 %. Hepatitis merupakan inflamasi hati dapat terjadi
karena invasi bakteri, cedera oleh agen fisik atau kimia (non-viral), atau infeksi
virus (hepatitis A, B, C, D, E). Hepatitis B disebabkan Hepatitis B Virus (HBV).
Beberapa komponen HBV maupun respon tubuh penderita terhadap infeksi HBV
yang dapat dipakai sebagai petanda serologi hepatitis virus B, misalnya HbsAg
dan anti HBs, HbcAg dan anti HBc, HbeAg dan anti Hbe, dan Hepatitis B Virus
DNA polimerase serta Hepatitis B Virus DNA spesifik. Masa inkubasi virus
tersebut berlangsung 2 sampai 6 bulan dengan gambaran klinik bervariasi, namun
sebagian besar gejalanya berupa ikterus. Walaupun secara klinis ringan, namun
sebagian akan menjadi kronis dan mengalami perkembangan menjadi sirosis
hepatis yang kemudian akan menjadi kanker hati. Penularannya dapat terjadi
secara per kutan dan non kutan, disamping itu juga dikenal penularan vertikal dan
horizontal. Penularan vertikal adalah penularan dari seorang Ibu pengidap
hepatitis B kepada bayinya sebelum persalinan, pada saat persalinan, atau
beberapa saat setelah persalinan. Sementara penularan horizontal adalah
3

penularan yang terjadi melalui transfusi darah yang terkontaminasi oleh HBV dan
pasien yang mendapat hemodialisa, selain itu dapat juga melalui luka pada kulit
dan selaput lendir, misalnya tertusuk jarum, menggunakan jarum suntik yang
kurang steril, menindik telinga, dan sebagainya (Yusuf, 1991).
Berdasarkan latar belakang tersebut, diidentifikasi permasalahan penelitian
mengenai komorbiditas (hepatitis) terhadap kualitas hidup penderita gagal ginjal
kronik terminal yang melakukan program hemodialisis di unit hemodialisis RSU
PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
B. Perumusan Masalah
Pertanyaan penelitian atau perumusan masalah penelitian ini adalah:
Bagaimana hubungan komorbiditas (hepatitis) dengan kualitas hidup penderita
gagal ginjal kronik terminal di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
C. Tujuan Penelitian
Mengetahui hubungan komorbiditas (hepatitis) dengan kualitas hidup
penderita gagal ginjal kronik terminal di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini akan memberikan kemanfaatan antara lain:
1. Menambah informasi dan ilmu pengetahuan tentang komorbiditas (hepatitis)
dengan kualitas hidup penderita gagal ginjal kronik terminal di daerah
Yogyakarta khususnya RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang sampai
saat ini masih kurang.
2. Memberikan informasi untuk para klinisi yang melaksanakan pelayanan
perawatan penderita gagal ginjal di RS dan para pimpinan atau pengambil
4

kebijakan tentang upaya peningkatan kualitas hidup penderita gagal ginjal
kronik dan pengelolaan penderita gagal ginjal kronik.
D. KEASLIAN PENELITIAN
Stuyver, et al. (1996) pernah melakukan penelitian berjudul ”Hepatitis C virus
in a hemodialysis unit: Molecular evidence for nosocomial transmission”. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah prospektif. Dari penelitian itu
disimpulkan bahwa dari 68 orang yang menjalani hemodialisis, 25 diantaranya
positif terdapat Hepatitis C Virus (HCV). Penelitian tersebut dilakukan di
Dendermonde, Belgium.
Burdick, et al. (2003) melakukan penelitian dengan judul ”Patterns of
Hepatitis B prevalence and seroconversion in hemodialysis unit from three
continents: The DOPPS”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah cross
sectional, prospective, observational pada beberapa Negara seperti Perancis,
Jerman, Itali, Jepang. Hasilnya, tiap negara mempunyai prevalensi Hepatitis B
Virus (HBV) yang berbeda.
Penelitian tentang komorbiditas hepatitis pada pasien gagal ginjal yang
mengalami hemodialisa sudah pernah dilakukan di luar Indonesia, namun
penelitian tentang komorbiditas (hepatitis) yang berhubungan dengan kualitas
hidup penderita gagal ginjal kronik terminal yang melakukan program
hemodialisis di unit hemodialisis RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta belum
pernah dilakukan.
5

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Telaah Pustaka
1. Definisi Gagal Ginjal kronik terminal (end stage renal disease).
Gagal ginjal adalah penyakit yang ditandai dengan adanya penurunan fungsi
ginjal. Penyakit gagal ginjal dibedakan menjadi gagal ginjal akut dan gagal ginjal
kronik. Penyakit gagal ginjal akut biasanya terjadi oleh karena adanya hipoksia
pra renal yang berakhir pada iskemia jaringan ginjal sehingga menyebabkan
kerusakan pada sel-sel tubulus ginjal dan menghambat atau mengganggu fungsi
penyaringan oleh glomerulus atau glomerulus filtration rate (GFR) menurun yang
bersifat sementara atau reversible (Levey et al., 2003).
Berbeda dengan gagal ginjal akut, pada gagal ginjal kronik kerusakan struktur
ginjal atau penurunan GFR bersifat irreversibel. Pengertian gagal ginjal kronik
adalah tidak normalnya struktur dan fungsi ginjal selama lebih dari 3 bulan
dengan manifestasi sbb (1). Kerusakan ginjal dengan atau tanpa penurunan GFR
yang dapat diketahui dari adanya gambaran kelainan histopatologis atau adanya
marker kerusakan ginjal, termasuk didalamnya adalah adanya abnormalitas
susunan darah atau susunan urin pada test mikroskopis dan (2). GFR <60
ml/min/1.73 m2,dengan atau tanpa kerusakan ginjal (Levey et al., 2003; Stevens
et al., 2006).
2. Patogenesis dan manifestasi klinik gagal ginjal kronik terminal
Pada keadaan dimana terjadi gangguan fungsi filtrasi dari ginjal biasanya
diikuti dengan kenaikan kadar kreatinin dan ureum darah. Sehingga manifestasi
6

klinik gagal ginjal kronik biasanya adalah merupakan manifestasi dari adanya
kerusakan struktur ginjal atau gangguan fungsi filtrasi ginjal, antara lain adanya
keluhan penurunan jumlah kencing yang dikeluarkan, kencing berwarna lebih tua,
adanya darah pada kencing, peningkatan ureum atau kretinin serta anemia yang
kadang-kadang membutuhkan hemodialisis. Penyakit gagal ginjal kronik yang
membutuhkan tindakan hemodialisis rutin atau transplantasi organ ginjal disebut
dengan penyakit gagal ginjal terminal atau end stage renal disease (ESRD).
Kriteria diagnosis gagal ginjal terminal adalah penurunan fungsi filtrasi
glomerulus yang dinyatakan dengan kliren kreatinin <5 ml/menit dan kadar
kreatinin serum lebih dari atau sama dengan 10 mg/dL (Mitch et al., 1990).
Perjalanan alamiah penyakit gagal ginjal dan strategi penanganannya serta
komplikasinya tampak pada gambar 1.
Gambar 1. Perjalanan alamiah penyakit gagal ginjal dan strategi penanganannya serta komplikasinya (Levey et al., 2003).
Terjadinya gagal ginjal progresif adalah diakibatkan oleh 3 hal yaitu
glomerulosklerosis, fibrosis tubulointerstisial dan sklerosis vaskular. Semua
7

bentuk gagal ginjal kronik berhubungan dengan kerusakan tubulointerstisial yang
nyata. Penyakit tubulointerstisial dapat menyebabkan atropi tubulus dan atau
obstruksi, bahkan mengakibatkan kehilangan nefron (Remuzi et al., 1998).
3. Epidemiologi gagal ginjal kronik terminal (End stage Renal Diseases)
Gagal ginjal kronik merupakan penyakit kronik yang menjadi salah satu
permasalahan utama kesehatan di masyarakat (Schoolwerth et al., 2006).
Penyakit gagal ginjal kronik telah mengalami epidemik, senantiasa terjadi
penambahan kasus baru yang semakin meningkat dari tahun ketahun sementara
kasus lama masih dalam perawatan dengan tingkat morbiditas dan mortalitas yang
besar. Gambaran kecenderungan peningkatan insidensi dan prevalensi gagal ginjal
kronik dan gagal ginjal terminal (ESRD) di Amerika tampak pada gambar 3.
Gambar 2. Kecenderungan peningkatan prevalensi dan insidensi gagal ginjal kronik dan ESRD di Amerika (Gilberston et al, 2005).
Di Amerika terjadi kenaikan tajam penderita gagal ginjal kronik dan gagal
ginjal terminal, kasus baru gagal ginjal terminal pada tahun 1978 kurang lebih
sebesar 14.500 sedangkan pada tahun 2002 naik menjadi 100.359. Kasus baru
8

ESDR pada tahun 2004 di Amerika serikat sebesar 104.000, naik 1,5% dari tahun
2003 sedangkan penderita yang mendapatkan dialisis sebanyak 336.000 atau naik
sebesar 3-4 % dari tahun 2003. Pada tahun 2004 di Amerika serikat prevalensi
penderita yang mendapatkan transplantasi ginjal sebanyak lebih dari 136.000 atau
naik 5-9 % dari tahun 2003. Pada tahun 2006 jumlah penderita gagal ginjal kronik
di Amerika adalah sebanyak 19,2 juta atau 11% dari populasi dewasa sedangkan
yang mengalami gagal ginjal terminal adalah sebesar 0,22% populasi
(Schoolwerth et al, 2006).
Rata-rata umur insidensi penderita ESRD di Amerika adalah 64,6 tahun. Pada
warga kulit hitam angka kejadian ESRD oleh karena diabetika mulai meningkat
pada kelompok umur 30-39 tahun, sedangkan pada warga kulit putih besarnya
angka kejadian ESRD adalah sama pada semua kelompok umur. Di Amerika
angka kejadian ESRD pada kaum laki-laki lebih tinggi dibandingkan pada wanita
(Schoolwerth et al., 2006).
Gambaran besarnya prevalensi pada berbagai gangguan fungsi ginjal
berdasarkan nilai GFR di Amerika tampak pada tabel 1.
9

Tabel 1. Tahap kerusakan ginjal dan hubungannya dengan GFR dan prevalensinya di masyarakat Amerika (Levey et al.,2003)
Tahap GambaranGFR
(ml/min/1.73 m2)
Prevalensi*
N (1000s) %
1Kerusakan ginjal
dengan GFR³ 90 5,900 3.3
2Kerusakan ginjal
dengan sedikit ¯ GFR60-89 5,300 3.0
3 ¯ GFR moderat 30-59 7,600 4.3
4 ¯ GFR berat 15-29 400 0.2
5 Gagal ginjal < 15 atau Dialysis 300 0.1
Gagal ginjal kronik terminal dapat mengakibatkan prematuritas dalam
kesakitan dan kematian serta penurunan kualitas hidup serta mahal dalam
perawatannya. Angka kematian akibat gagal ginjal kronik terminal di Amerika
serikat mencapai 71.000 pada tahun 2000 dan diperkirakan akan meningkat
mencapai 352.000 pada tahun 2030 (Schoolwerth et al., 2006).
Insidensi gagal ginjal kronik terminal di Taiwan adalah tinggi. Telah terjadi
kenaikan tajam insidensi Chronic Kidney Disease (CKD) di Taiwan dari 1,99 %
pada tahun 1996 menjadi 9,83 % pada tahun 2003. Angka insidensi CKD di
Taiwan tahun 2003 adalah sebesar 135 tiap 10.000 orang per tahun. Faktor-faktor
yang berhubungan dengan kejadian CKD di Taiwan adalah umur (OR=13,95
untuk di atas 75 tahun dibandingkan 20 tahun), diabetes melitus, hipertensi,
hiperlipidemi dan jenis kelamin wanita (Kuo et al., 2007).
10

Di Jepang telah terjadi kenaikan tiga kali lipat pengguna renal replacement
therapy (RRT) antara 1983-2000, sehingga jumlah pengguna RRT pada tahun
2000 mencapai lebih dari 31.000 orang. Di Jepang kejadian ESRD pada kelompok
laki-laki lebih besar dibandingkan pada kelompok wanita. Insidensi ESRD di
Jepang tertinggi terjadi pada kelompok umur 80-84 tahun yaitu sebesar 1432 tiap
1 juta penduduk untuk laki-laki dan 711 tiap 1 juta penduduk untuk wanita
(Wakai et al., 2004).
Penelitian epidemiologi multi negara oleh The ESRD Incidense Study Group
menunjukkan bahwa insiden ESRD di negara-negara Asia dan negara berkembang
lainnya adalah lebih tinggi dibandingkan negara di Eropa, meskipun lebih rendah
dibandingkan dengan insidensi ESRD di Australia dan New Zealand. Gambaran
Age-and sex standardized incidense rates (ASR) ESDR di Malaysia pada berbagai
kelompok yaitu kelompok umur 0 -14 tahun adalah 96 tiap 1 juta penduduk, 15-
29 tahun adalah 26 tiap 1 juta penduduk, 30-44 tahun adalah 77 tiap 1 juta
penduduk dan 45-64 tahun adalah 306 tiap 1 juta penduduk (The ESRD Incidense
Study Group, 2006).
Sebagaimana di negara-negara berkembang lainnya, insidensi dan prevalensi
gagal ginjal kronik terminal di Indonesia juga belum diketahui dengan pasti.
Besarnya insidensi gagal ginjal kronik terminal di Indonesia diperkirakan sebesar
100-150 orang tiap 1 juta penduduk pertahun. Besarnya prevalensi gagal ginjal
kronik terminal di Indonesia diperkirkan sebesar 200 – 250 orang tiap 1 juta
penduduk pertahun. Besarnya insidensi dan prevalensi gagal ginjal kronik dan
ESRD di Yogjakarta juga belum diketahui (Bakri, 2005).
11

4. Faktor Risiko Gagal Ginjal Kronik
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kejadian gagal ginjal kronik. Dari
hasil penelitian, faktor-faktor yang diduga berhubungan dengan kejadian dan
progresifitas penyakit gagal ginjal kronik antara lain umur, jenis kelamin, etnik,
berat lahir rendah, berat badan, status sosial ekonomi, merokok, tekanan darah,
kholesterol darah, alkohol dan obat terlarang lainnya, obat analgetika & NSAID,
dan diabetes. Sedangkan yang menjadi penanda utama penyakit gagal ginjal
adalah CRP, pro-BNP , Hemoglobin, GFR dan albuminuria (Agarwal et al.,
2005; Kasiske et al., 2000; Clelan et al., 2003; Haroun et al., 2003; Schwartz et
al., 1999; Sietsma et al., 2000).
Berdasarkan sifat dapat atau tidaknya faktor-faktor tersebut untuk diubah,
faktor risiko gagal ginjal kronik dibagi menjadi tiga yaitu faktor risiko yang tidak
dapat diubah atau diobati, faktor risiko yang dapat diubah dan faktor risiko yang
dapat diobati. Diduga termasuk faktor risiko gagal ginjal kronik yang dapat
diubah melalui pendidikan antara lain merokok, berat bayi lahir rendah, minum
alkohol dan penggunaan obat-obatan terlarang lainnya, perilaku hidup tak sehat,
paparan zat-zat toksik dan penyalah gunaan obat-obatan analgetik (Fored, 2003).
Termasuk dalam faktor risiko gagal ginjal kronik yang dapat diobati adalah
tekanan darah tinggi, kencing manis, dislipidemia dan proteinuria (Chen et al.,
2004; Retnakaran et al., 2006) sedangkan faktor risiko yang tidak dapat diubah
dan diobati adalah jenis kelamin, ras atau etnik dan umur (Fored, 2003).
Akhir-akhir ini mulai terjadi kecenderungan baru penyakit gagal ginjal yaitu
banyak anak muda usia mulai dijangkiti gagal ginjal kronik. Penyakit gagal ginjal
12

yang dulunya banyak dialami oleh orang-orang yang lebih tua atau di atas 40
tahun saat ini banyak dialami oleh orang yang berumur kurang dari 40 tahun
bahkan anak-anak yang berumur belasan tahun. Sejak tahun 2005, kurang lebih 25
persen dari penderita gagal ginjal yang menjalani terapi hemodialisis di RS PKU
berusia kurang dari 40 tahun.
5. Quality Of Life atau Kualitas Hidup
Kualitas hidup pasien seharusnya menjadi perhatian penting bagi para
professional kesehatan karena dapat menjadi acuan keberhasilan dari suatu
tindakan/intervensi atau terapi. Disamping itu, data tentang kualitas hidup juga
dapat merupakan data awal untuk pertimbangan merumuskan intervensi/tindakan
yang tepat bagi pasien. Kualitas hidup adalah persepsi seseorang tentang
posisinya dalam hidup dalam kaitannya dengan budaya dan sistem tata nilai di
mana ia tinggal dalam hungannya dengan tujuan, harapan, standar, dan hal-hal
menarik lainnya. WHO mendefinisikan kualitas hidup sebagai “the individual’s
perception of their life status concerning the context of culture and value system
inwhich they live and their goals, expectations, standards,and concerns”.
Penderita GGKT yang menjalani hemodialisis sering diikuti dengan penurunan
kualitas hidup. Dari penelitian sebelumnya beberapa faktor yang berhubungan
dengan kualitas hidup pasien antara lain adanya rasa nyeri dan ketidaknyamanan
yang diakibatkan dari sakit yang diderita atau tindakan atau prosedur pengobatan
terkait sakit yang diderita, gangguan tidur, kualitas pelayanan dan perawatan,
penyakit penyerta, status sosial ekonomi dan dukungan keluarga (Cohen et al.,
2007; Joan et al., 2004; Scot et al., 2007; Nelson et al., 1999).
13

Saat ini health-related quality of life (HRQOL) atau kualitas hidup yang
berhubungan dengan kesehatan telah menjadi salah satu ukuran dari keberhasilan
pelayanan kesehatan. Pengukuran HRQOL bersifat multidimensi yang meliputi
antara lain fungsi fisik, sosial dan fungsi peran , mental health dan persepsi
kesehatan secara umum. Pengukuran kualitas hidup dapat dilakukan dengan
menggunakan kuesioner kualitas hidup dari WHO (Albert et al., 2004; Bayliss et
al., 2005).
6. Komorbiditas Hepatitis
Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi kualitas hidup penderita Gagal
Ginjal Kronik Terminal (GGKT) adalah komorbiditas atau penyakit penyerta,
contohnya diabetes, penyakit jantung, hepatitis, dan sebagainya. Hepatitis sebagai
komorbiditas GGKT dapat merupakan infeksi nosokomial akibat hemodialisis.
Dialisis merupakan satu-satunya cara mempertahankan kelangsungan hidup
pasien dengan tujuan menurunkan kadar ureum, kreatinin, dan zat-zat toksik
lainnya dalam darah. Hemodialisis lebih sering dilakukan dibanding peritoneal
dialisis. Pada hemodialisis, darah pasien dipompa keluar dari pembuluh darah,
masuk ke dalam suatu alat, akan terjadi proses difusi melalui membran
semipermeabel untuk membuang zat-zat toksik dalam darah. Akhir-akhir ini,
dengan makin mahalnya peralatan hemodialisis, penggunaan ulang komponen-
komponen pada unit hemodialisis makin meningkat. Sebagian besar (81%)
hemodialisis di AS menggunakan ulang alat dialisis. Di Australia 35%, di
Portugal 77%, di Polandia 88%, bahkan di Bulgaria 100%. Sebaliknya negara
Eropa lain tidak banyak menggunakan ulang alat dialisis. Di Inggris hanya 10%,
14

di Perancis 6%, di Jerman 5%, di Spanyol 3%. Bahkan Austria, Belanda,
Finlandia, dan Swedia tidak menggunakan ulang (Loho, 2000; Siswono, 2001).
Infeksi yang terjadi pada pasien hemodialisis dapat berasal dari sumber air
yang dipakai, sistem pengolahan air pada pussat dialisis, sistem distribusi air,
cairan dialisat, serta mesin dialisis. Komplikasi tersering kontaminasi cairan
dialisis adalah reaksi pirogenik dan sepsis yang disebabkan bakteri gram negatif.
Selain itu, infeksi dapat juga terjadi oleh mikroorganisme yang ditularkan melalui
darah seperti virus hepatitis B (HBV), human immunodeficiency virus (HIV), dan
lain-lain. Infeksi merupakan penyebab utama meningkatnya angka kesakitan dan
angka kematian pada pasien hemodialisis. Penyebab tingginya infeksi pada pasien
GGKT adalah menurunnya sistem imun, adanya penyebab sekunder (diabetes,
penyakit jantung, dan lain-lain) yang pada akhirnya memperberat resiko infeksi
(Loho, 2000).
Hepatitis adalah merupakan inflamasi hati dapat terjadi karena invasi bakteri,
cedera oleh agen fisik atau kimia (non-viral), atau infeksi virus (hepatitis A, B, C,
D, E). Agen infeksi menetap dan mengakibatkan peradangan dan kerusakan se-
sel hati. Akibatnya terjadi penurunan penyerapan dan konjugasi bilirubin sehingga
terjadi disfungsi hepatosit dan mengakibatkan ikterik, peradangan ini akan
mengakibatkan peningkatan suhu tubuh, hiperpermeabilitas sehingga terjadi
pembesaran hati, hal ini dapat diketahui dengan meraba atau palpasi hati. Nyeri
tekan dapat terjadi pada saat gejala ikterik mulai nampak. Hepatitis viral dapat
dibagi menjadi dua kelompok yaitu kronik dan akut. Klasifikasi hepatitis viral
akut dapat dibagi atas hepatitis akut viral yang khas, hepatitis yang tak khas
15

(asimtomatik), hepatitis viral akut yang simtomatik, hepatitis viral anikterik dan
hepatitis viral ikterik. Hepatitis virus kronik dapat diklasifikasikan dalam 3
kelompok yaitu hepatitis kronik persisten, hepatitis kronik lobular, dan hepatitis
kronik aktif (Muhaj, 2009).
Hepatitis B adalah penyakit radang hati yang disebabkan Virus Hepatitis B
(VHB). Beberapa komponen Hepatitis Virus B maupun respon tubuh penderita
terhadap infeksi VHB yang dapat dipakai sebagai petanda serologi hepatitis virus
B, misalnya HbsAg dan anti HBs, HbcAg dan anti HBc, HbeAg dan anti Hbe, dan
Hepatitis Virus B DNA polimerase serta Hepatitis B Virus DNA spesifik. Masa
inkubasi virus tersebut berlangsung 2 sampai 6 bulan dengan gambaran klinik
bervariasi, namun sebagian besar gejalanya berupa ikterus. Walaupun secara
klinis ringan, namun sebagian akan menjadi kronis dan mengalami perkembangan
menjadi sirosis hepatis yang kemudian akan menjadi kanker hati. Penularannya
dapat terjadi secara per kutan dan non kutan, disamping itu juga dikenal penularan
vertikal dan horizontal. Penularan vertikal adalah penularan dari seorang Ibu
pengidap hepatitis B kepada bayinya sebelum persalinan, pada saat persalinan,
atau beberapa saat setelah persalinan. Sementara penularan horizontal adalah
penularan yang terjadi melalui transfusi darah yang terkontaminasi oleh VHB dan
pasien yang mendapat hemodialisa, selain itu dapat juga melalui luka pada kulit
dan selaput lendir, misalnya tertusuk jarum, menggunakan jarum suntik yang
kurang steril, menindik telinga, dan sebagainya (Yusuf, 1991).
7. Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
16

Penelitian komorbiditas hepatitis pada pasien GGKT ini menggunakan metode
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA). ELISA merupakan tekhnik
biokimia yang digunakan dalam imunologi terutama untuk mendeteksi
keberadaan sebuah antibodi atau antigen dalam sampel. Ciri utama ELISA adalah
dipakainya indikator enzim untuk reaksi imunologi. Prinsip dasar uji ELISA
adalah ikatan antara antigen dengan antibodi yang homolog. ELISA mempunyai
sensivitas dan spesifisitas yang tinggi. Dalam hubungannya dengan deteksi
antigen, sensitivitas dapat diartikan sebagai sejumlah antigen yang dapat
dideteksi, dan spesifitas adalah suatu kemampuan untuk membedakan senyawa-
senyawa tertentu. Konfigurasinya meliputi ELISA langsung, ELISA tak langsung,
ELISA penangkap antigen atau ELISA sandwich, ELISA penangkap antibodi,
ELISA kompetitf atau ELISA pemblok (Burgess, 1995; Agustini et al., 2005).
8. Komorbiditas hepatitis dan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik
Kesehatan mempengaruhi kualitas hidup dalam berbagai hal, yaitu gejala
penyakit yang dapat mengganggu aktivitas, fungsi sosial, mental, dan lain-lain.
Adanya komorbiditas hepatitis pada pasien gagal ginjal kronik tentu saja akan
memperburuk kualitas hidupnya. Hepatitis awalnya tidak menimbulkan gejala
klinis yang membahayakan, namun seiring berjalannya waktu, jika tidak diterapi
dengan baik dapat berkembang menjadi kanker hati yang nantinya dapat
mengakibatkan kematian pada pasien tersebut. Pasien tersebut selama hidupnya
tidak hanya mengalami gangguan karena kerusakan ginjal, tetapi juga akan
mengalami gangguan karena kerusakan hati. Ginjal dan hati adalah organ yang
penting dalam tubuh. (Muhaj, 2009; Yusuf 1991; Merkus et al., 1997)
17

B. Kerangka Konsep
Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah:
Gambar 3. Kerangka konsep penelitian tentang hubungan komorbiditas hepatitis dengan kualitas hidup pada gagal ginjal kronik terminal.Keterangan: - - - - - - - yang diteliti
________ yang tidak diteliti
C. Hipotesis
Terdapat hubungan komorbiditas hepatitis dengan kualitas hidup penderita
gagal ginjal kronik terminal di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
BAB III
METODE PENELITIAN
18
Faktor Penyakit Komorbid:Diabetes Melitus, Hipertensi,
Penyakit Jantung Koroner
Faktor Penyakit Komorbid:Hepatitis
Faktor Penyakit Faktor Merokok
Faktor Obat-obatan Faktor Makanan
Gagal Ginjal Kronik Terminal
Kualitas HidupGagal Ginjal Kronik
Terminal
Faktor lainKepuasan pasienPerilaku merokokFungsi keluarga

A. Jenis dan rancangan penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan rancangan
cross sectional.
B. Lokasi penelitian
Penelitian dilaksanakan di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta. RSU
PKU Muhammadiyah merupakan salah satu dari 4 rumah sakit di DIY yang
mempunyai pusat hemodialisis.
C. Subjek penelitian
1. Batasan populasi
Populasi adalah pasien yang terdiagnosis gagal ginjal kronis terminal,
dengan kriteria diagnosis yaitu kliren kreatinin <5ml/menit atau kadar
kreatinin serum darah lebih besar atau sama dengan 10 mg/dl yang dapat
diketahui dari rekam medis dan memerlukan hemodialisa secara kontinyu.
Kriteria inklusi subyek penelitian :
a.Orang Indonesia (Jawa, Sunda, Melayu)
b.Usia 15-75 tahun
c.Bersedia berpartisipasi dalam penelitian dengan mengisi dan
menandatangani lembar pernyataan persetujuan serta kooperatif.
Kriteria eksklusi subyek penelitian
Subyek penelitian yang telah terpilih melalui kriteria inklusi akan
dikeluarkan dari subyek penelitian apabila :
a.Memiliki penyakit ginjal bawaan
b.Riwayat transplantasi ginjal
19

c.Penyakit jiwa, dari riwayat pernah didiagnosis oleh dokter jiwa
2. Besar sampel
Besar sampel dihitung dengan menggunakan rumus penentuan besar
sampel untuk pengujian hipotesis menurut Lemeshow at al (1997) sebagai
berikut :
N =Z1-/2 ².p.q
d2
p = 0,02, proporsi penderita gagal ginjal kronik terminal di Indonesia
(Bakri, 2005).
q = 0,98
dengan : tingkat kemaknaan 95%; Z1-/2 = 1,96.
d (tingkat presisi)= 0,03 atau kesalahan maksimum yang diperbolehkan
Maka didapatkan nilai N = 83,66, dibulatkan = 84
Antisipasi terhadap kesalahan dan kegagalan dalam proses penelitian,
jumlah sampel ditambah dengan 10% dari sampel minimal yaitu 8,4 atau
dibulatkan menjadi 9, sehingga jumlah sampel minimal yang dibutuhkan
adalah 93 orang.
3. Cara pengambilan sampel.
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara random sampling.
4. Alat dan bahan.
20

Alat dan bahan dalam penelitian ini meliputi perlengkapan pemeriksaan
elisa meliputi antara lain bahan kimia dan perkakas gelas sbb: Natrium
karbonat (Na2CO3), Natrium bikarbonat (NaHCO3), Natrium klorida
(NaCl), Kalium hydrogen fosfat (KH2PO4) Natrium hydrogen fosfat
(NaHPO4) Kalium klorida (KCl), tween 20, asam sitrat, Natrium fosfat
(Na2HPO4), orthophenylene diamine, hirogen peroksida (H2O2) 30 %,
Asam sulfat (H2SO4) 2,5 M dan conjugate. Microplatedasar datar 2 buah,
masing-masing terdiri dari 96 sumuran. Mikropipet yang telah dikalibrasi
2 buah, masing-masing berukuran 10 - 100 µl dan 100 - 1000 µl.
Mikrospektrofotomeeter (Mico elisa reader). Pipet ukur 1 ml. Spuit 2,5 ml
untuk mengambil darah dari vena. Venoject untuk menampung darah dan
menyimpan serum dan sarung tangan.
D. Variabel penelitian
Variabel dalam penelitian ini yaitu:
1.Variabel terpengaruh : Kualitas hidup penderita gagal ginjal kronik
terminal.
2.Variabel pengaruh : Komorbid (hepatitis)
E. Definisi operasional
1. Gagal ginjal kronik terminal adalah gangguan fungsi ginjal menetap
(lebih dari 3 bulan) dan memerlukan transplantasi ginjal atau tindakan
dialisis rutin untuk menggantikan fungsi ginjal, kelainan ginjal diukur
dengan penurunan kliren kreatinin yaitu kliren kreatinin<5 ml/menit
atau kadar kreatinin serum lebih dari atau sama dengan 10 mg/dL
21

(Mitch et al., 1990). YA apabila responden memenuhi kriteria
laboratorium atau memerlukan transplantasi ginjal atau menjalani
hemodialisa. TIDAK apabila responden tidak memenuhi kriteria
laboratorium atau memerlukan transplantasi ginjal atau menjalani
hemodialisa.
2. Kualitas hidup sangat dipengaruhi kesehatan. Contohnya adalah gejala
penyakit yang dapat mengganggu aktivitas, fungsi sosial, mental
penderita. Kualitas hidup penderita gagal ginjal kronik terminal tentu
mengalami penurunan, apalagi jika terdapat adanya komorbid hepatitis
pada pasien gagal ginjal kronik, tentu saja hal tersebut akan
memperburuk kualitas hidupnya. Hepatitis awalnya tidak menimbulkan
gejala klinis yang membahayakan, namun seiring berjalannya waktu,
jika tidak diterapi dengan baik dapat berkembang menjadi kanker hati
yang nantinya dapat mengakibatkan kematian pada pasien tersebut. YA
apabila penyakit gagal ginjal kronik mempengaruhi kualitas hidup
responden. TIDAK apabila penyakit gagal ginjal kronik tidak
mempengaruhi kualitas hidup responden.
3. Komorbid adalah penyakit penyerta yang dialami oleh penderita gagal
ginjal kronik terminal. Komorbid yang diamati adalah penyakit
hepatitis. Penetapan infeksi hepatitis dilakukan dengan pemeriksaan
serologi untuk menentukan ada tidaknya marker infeksi hepatitis
dengan metode ELISA. YA apabila responden memenuhi kriteria
22

positif HBSAg. TIDAK apabila responden tidak memenuhi kriteria
positif HBSAg.
F. Alat ukur penelitian
Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
1. Kuesioner, dipergunakan untuk mendapatkan data primer dari
responden tentang data komorbid yang di dapatkan dari pemeriksaan
laboratorium dengan metode ELISA serta kualitas hidup responden.
2. Form pengambilan data, dipergunakan untuk mengumpulkan data
sekunder yang diambil dari buku medical record atau status pasien
yang meliputi nama, umur, jenis kelamin, data diagnosis sakit dan
medikasi terdahulu, data-data laboratorium serta manifestasi klinik
penderita.
G. Jalannya penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut:
1. Tahap persiapan:
a. mengurus izin penelitian
b. mengumpulkan data sekunder meliputi gambaran umum RSU PKU
Muhammadiyah, angka kunjungan, jenis penyakit prioritas, angka
kejadian gagal ginjal dan gagal ginjal kronik di RSU PKU Yogyakarta
dari rekam medik dan sumber-sumber lain, uji coba instrumen
kuesioner.
c. membuat protokoler cara pengisian kuesioner kepada anggota
numerator dan pelatihan cara pengisiannya.
23

d. menetapkan pelaksanaan dan menyiapkan alat dan atau bahan
penelitian seperti alat tulis-menulis, kuisioner, form pengambilan data.
2. Tahap pelaksanaan
Tahap pelaksanaan meliputi kegiatan di lapangan maupun di laboratorium
sebagai berikut:
a. Pengambilan data primer pada sampel dengan wawancara dengan
menggunakan kuesioner meliputi identitas responden, sosial ekonomi,
tentang data komorbid yang di dapatkan dari rekam medis penderita,
kualitas hidup responden.serta data lain yang terkait dengan variabel
penelitian.
b. Pengambilan data primer dengan pemeriksaan elisa di laboratorium
untuk mengetahui ada tidaknya infeksi hepatitis, dengan prosedur
sebagai berikut:
(1). Pengambilan sampel darah. Darah responden diambil sebanyak 5
ml oleh petugas rumah sakit. Jumlah sampel darah yang diambil
adalah 96 sampel/orang dari respoden. Pengambilan darah dilakukan
pada fosa kubiti dengan spuit injeksi ukuran 5 ml dengan menjaga
aspek keamanan dan sterilitas. Sampel darah dimasukkan dalam
tabung yang sudah diberi label yang berisi nomor kode tabung, nama,
jenis kelamin dan umur responden, kemudian dimasukkan dalan
termos berisi coldpack dibawa ke laboratorium untuk dilakukan
pemeriksaan marker hepatitis;
24

(2). Pemeriksaan marker hepatitis secara elisa untuk deteksi anti
HBSAg.
Darah sampel dibiarkan menjendal dan setelah menjendal segera
disentrifus dengan kecepatan 1500 rpm selama 15 menit. Setelah
serum nampak terpisah, venoject yang berisi serum tersebut segera
disimpan di dalam freezer dan serum tersebut baru diambil setelah
pengujian serologis dengan ELISA siap dikerjakan. Persiapan
pemeriksaan Elisa : (a). Diambil mikroplate yang telah dilapisi antigen
hepatitis, per well berisi 100 µl berisi 0,5 µg antigen, kemudian
disimpan 1 malam. (b). Cuci dengan PBS Tween 20 seanyak 3 x
dalam 1 menit. (c). Blocking dengan BSA 1 % sebanyak 100 µl
kemudian inkubasikan selama 1 jam. (d). Cuci lagi dengan PBS
Tween 3x selama 1 menit. (e). Masukkan serum darah dengan
perbandingan 1:100 dengan PBS, masukkan 100 µl tiap well dan
diinkubasi selama 1 jam. (f). Cuci dengan PBS Tween 20 sebanyak 3
x dalam 1 menit. (g). Masukkan conjugate dengan perbandingan
1:2000, kemudian diinkubasi selama 1 jam. (h). Cuci dengan PBS
Tween 20 sebanyak 3x selama 1 menit. (i). Masukkan substrat 100 µl,
nitrofenil fosfat untuk conjugate alkalin fosfatase atau
orthophenildiaminase untuk conjugate dengan peroksidase. Kemudian
diinkubasikan selama 1/2 jam. (j). Stop reaksi dengan NaOH 3 M,
kemudian dibaca dengan ELISA reader pada panjang gelombang 405.
25

3. Tahap akhir. Pengolahan data, analisis data, presentasi hasil serta
pembuatan laporan dan publikasi laporan.
H. Cara analisis data
Mencari hubungan antara komorbiditas dengan kualitas hidup penderita
gagal ginjal kronik terminal di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta,
dilakukan dengan uji kai kuadrat dan analisis multivariate dengan regresi
logistik.
Data yang diperoleh diolah menggunakan tabel 2x2 dan dianalisis dengan uji
kai kuadrat untuk mengetahui relative risk dan menilai adanya hubungan antara
faktor yang diteliti dengan kualitas hidup penderita gagal ginjal kronik. Sete-
lah diketahui nilai relative risk masing-masing faktor kemudian dilanjutkan
dengan analisis multivariate dengan menggunakan regresi logistik.
I. Etika Penelitian
Karena melibatkan responden manusia maka akan dilakukan penjelasan
kepada seluruh calon responden tentang maksud dan tujuan penelitian, manfaat
dan kegunaan yang diharapkan dan konsekuensi-konsekuensi sebagai
responden (informed consent).
J. Rencana waktu penelitian
Rencana kegiatan penelitian tampak pada tabel 2.
26

Tahapan Kegiatan Rencana waktu(bulan ke)
1 2 3Persiapan 1. Pengurusan ijin, penetapan pro-
tokoler & prosedur kerja2. Pengadaan bahan dan alat
3. Pengumpulan data sekunderPelaksanaan 1.Pengumpulan data primer di rumah sakit
dengan wawancara2.Pengumpulan data observasional
3.Pemeriksaan laboratorium dengan metoda Elisa
Akhir 1. Penulisan laporan 2. Seminar hasil 3. Penyerahan laporan
4. Publikasi
Tabel 2. Jadwal Kegiatan penelitian hubungan hipertensi, merokok dan minuman suplemen energi dengan kejadian gagal ginjal kronik.
27

Daftar Pustaka
Agarwal, R., Andersens, M.J., 2005. Correlates of systolic hypertension in patients with chronic kidney disease, Hypertension. J Am Soc Nephrol, 46: 514-520
Albert, W., Nancy, E., Jane, V.R., Marsh, M., Klemens, B.M., Frederic, O.F., Michelle, M.C., NEIL, R.P., 2004. Changes in Quality of Life during hemodialysis and Peritoneal Dialysis Treatment: Generic and Disease Specific Measures. J Am Soc Nephrol 15: 743–753,
Bakri, S., 2005. Deteksi dini dan upaya-upaya pencegahan progresifitas penyaki gagal ginjal kronik, Jurnal Medika Nusantara, 26(3):36-39
Bayliss, EA., Ellis, JL., Steiner, JF., 2005. Subjective assessments of comorbidity correlate with quality of life health outcomes: Initial validation of a comorbidity assessment instrument, Health and quality of life outcomes
Burdick, RA., Gresham, JL., Woods, JD., Hedderwick, SA., Kurokawa, K., Combe, C., Saito, A., BrecQue, JL., Port, FK., Young, EW., 2003. Patterns of hepatitis B prevalence and seroconversion in hemodilysis units from three continents: The DOPPS, Kidney international J, vol. 63, pp. 2222-2229.
Burgess, G.W. (1995). Tekhnologi ELISA dalam diagnosis dan penelitian. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Chen, J., Muntner, P., Hamm, L., Jones, D.W., Batuman, V., 2004. The metabolic syndrome and chronic kidney disease in U.S. adults, Ann Intern Med, 140:167-174.
Cohen, SD., Patel, SS., Khetpal, P. Peterson, RA., Kimmel, PL., 2007. Pain, sleep disturbance, and quality of life in patients with chronic kidney disease, Clin J Am Soc nephrol 2: 919-925
Fored, M. 2003. Risk factors for the development of chronic renal failure, Stockholm, Karolinska University Press
Go, A.S., Chertow, G.M., Fan, D., Hsu, C.Y., 2004. Chronic kidney disease and the risk of death, cardiovascular events and hospitalization, NEJM, 351:1296-305
28

Joan M. Teno; Brian R. Clarridge; Virginia Casey; et al, 2004. Family Perspectives on End-of-Life Care at the Last of Care. JAMA;291(12):1446.
Kasiske, B.L.& Klinger, D. 2000. Cigarette smoking in renal transplant recipients; J.Am Soc Nephrol;11:753-9
Kher, V., 2002. End stage renal disease in developing countries, J. Kidney
International, 62:350-362
Kuo, H.W., Tsai, S.S., Tiao, M.M., Yang, C.Y., 2007. Epidemiological features of CKD in Taiwan, Am J Kidney Dis, 49:46-55
Lemeshow, S., Hosmer, Jr. D.W., Klar, J., Iwanga, S.K., 1997. Besar sampel dalam penelitian kesehatan. Terjemahan.Cetakan pertama. Jogjakarta:Gadjah Mada University Press
Levey, A.S., Coresh, J., Balk, E., Kaustz, A.T., Levin, A., 2003. National Kidney Foundation practice guidelines for chronic kidney disease: evaluasi, klasifikasi and stratification; Ann Intern Med; 139:137 – 147
Loho, T., Pusparini. (2000). Infeksi nosokomial pada hemodialisis. Majalah Kedokteran Indonesia, 50 (3), 132-144
Mcclellan, W.M.& Flanders, W.D. 2003. Risk Factor for progressive chronic kidney disease; J Ant Soc Nephrol;14:s65-s70
Merkus, M.P., Jager, J.K., Dekker, F.W., Boeschoten, E.W., Stevens, P., Krediet, R.T., et al. (1997). Quality of life in patient on chronic dyalisis: self assessment 3 months after the start of treatment. American Journal of Kidney Disease, 29 (4), 584-592
Mitch, W.E., Bender, W.L., Walker, W.G., 1990. Management of progressive and end –stage renal disease dalam The principles and practice of medicine, Maryland
Nelson, C.B., & Lotfy, M. (1999). The World Health Organization’s WHOQoL-BREFquality of life assessment: psychometric properties and results of the internationalfield trial. WHO (MNH/MHP/99.7). Retrieved November 28th,2002, http://www.who.int/msa/qol/documents/WHOQOL_BREF.pdf
Remuzzi, G., Bertani, T. 1998. Pathophysiology of Progressive Nephropathies.
NEJM; 59:1448-1456.
29

Remuzzi,G., Ruggenenti, P., Perico, N. 2002. Chronic renal diseases Renoprotective benefits of Renin-angiotensin System Inhibition, Annual of Internal Medicine;136(8):604-615
Retnakaran, R., Cull, C.A., Thorn, K.I., Adler, A.I., Holman, R.R. 2006. Risk factors for renal dysfunction in type type 2 Diabetes; Diabetes;55:1832-9
Schoolwerth, A.C., Engelgau, M.M., Hostetter, T.H., Rufo, K.H., McClelan, W.M., (2006). Chronic kidney disease a publik health problem that needs a public health action plan, Prevention Chronic Disease, 3(2):1-5
Scott D. Cohen, Samir S. Patel, Prashant Khetpal, Rolf A. Peterson, and Paul L. Kimmel, (2007). Pain, Sleep Disturbance, and Quality of Life in patients with Chronic Kidney Disease, Clin J Am Soc Nephrol 2: 919-925,
Siestma, S.J.P., Mulder, J., Janssen, W.M.T., Hillege, H.L., (2000). Smoking is
related to abnormal renal function in nondiabetic persons, Ann Intern Med;133:585-91
Stevens, L.A., Coresh, J., Greene, T., Levey, A.S., (2006). Assesing kidney function-measured and estimated glomerular filtration rate, NEJM, 354:2473-83
Stuyver, L., Claeys, H., Wyseur, A., Arnhem, VA., Beenhouwer, HD., Uytendaele, S.,Beckers, J., Matthijs, D., Roels, GL., Maertens, G., Paepe, MD., (1996). Hepatitis C virus in hemodialysis unit : Moleculer evidence for nosocomial transmission, Kidney international, vol 49, pp. 889-895.
The ESRD Incidence Study Group, (2006). Geographic, etnic, age-related and
temporal variation in the incidence of end-stage renal disease in Europ, Canada and the asia-Pacific region, 1998-2002, NDT, 21:2178-2183
Wakai, K., Nakai, S., Kikuchi, K., Iseki, K., Miwa, N., Masakane, I., Wada, A.,
Shinzato, T., Nagura, Y., Akiba, T., (2004). Trends in incidence of end-stage renal disease in japan, 1983 – 2000, age-adjusted and age-speciphic rates by gender and cause, Nephrology Dialysis Transplantation, 19:2044 – 2052
Yusuf, (1991). Hubungan antara penggunaan jarum suntik dan jarum lain dengan kejadian Hepatitis B Virus. Berita Kedokteran Masyarakat, 60-63
30

Lampiran 1. Informed consent
INFORMED CONSENT
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Umur :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Bersedia ikut menjadi responden untuk penelitian tentang gagal ginjal kronik
terminal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh adanya
penyakit komorbid terhadap kualitas hidup penderita gagal ginjal kronik terminal.
Dengan alasan apapun apabila saya menghendaki maka saya berhak
membatalkan surat persetujuan ini. Demikian surat persetujuan ini saya buat
dengan sebenarnya, tanpa ada unsur paksaan.
Yogyakarta
Mengetahui, Peneliti Yang membuat pernyataan
Dita Windarofah -----------------------------------
31

Lampiran 2. Kuesioner penilaian kualitas hidup
Kuesioner penilaian kualitas hidup responden
WHOQOL-BREF
Pertanyaan berikut ini menyangkut perasaan anda terhadap kualitas hidup, kesehatan dan hal lain dalam hidup anda. Saya akan membacakan setiap pertanyaan kepada anda, bersamaan dengan pilihan jawaban. Pilihlah jawaban yang menurut anda paling sesuai. Jika anda tidak yakin tentang jawaban yang akan anda berikan terhadap pertanyaan yang diberikan, pikiran pertama yang muncul pada benak anda seringkali merupakan jawaban yang terbaik. Camkanlah dalam pikiran anda segala standar hidup, harapan, kesenangan dan perhatian anda. Kami akan bertanya apa yang anda pikirkan tentang kehidupan anda pada empat minggu terakhir.
Pertanyaan berikut adalah tentang seberapa sering anda telah mengalami hal-hal berikut ini dalam empat minggu terakhir.
32

Pertanyaan berikut ini adalah tentang seberapa penuh anda alami hal-hal berikut
ini dalam 4 minggu terakhir?
33

Pertanyaan berikut merujuk pada seberapa sering anda merasakan atau mengalami hal-hal berikut dalam empat minggu terakhir.
[Tabel berikut ini harus dilengkapi setelah wawancara selesai]
34

35