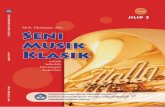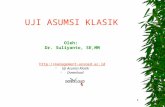(THI 300803) Classical Realism/Realisme Klasik
Transcript of (THI 300803) Classical Realism/Realisme Klasik
Disusun oleh
Iqbal Maulana Saputra
Hendri Satrio
Madinnatul Ulfa Nurjanah
Rorien Novriana
Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2014
Classical Realism
A. What is Realism?
Realisme klasik, atau sering disebut juga dengan Realisme adalah salah satu cabang
dari teori Positivisme, yakni teori yang percaya bahwa Ilmu HI, termasuk ilmu-ilmu
sosial lainnya dapat disetarakan dengan ilmu alam. Maka, jika hendak menguji dengan
maksud ingin menilai suatu teori, tidak boleh bersifat a priori (hanya berdasarkan teori
tanpa analisis yang memadai) dan abstrak, melainkan harus bersifat empiris dan
pragmatis. Dengan kata lain, kita tidak boleh menilai dengan suatu prinsip abstrak yang
sudah ditentukan sebelumnya, atau menggunakan konsep yang tidak ada hubungannya
dengan realitas, melainkan harus membawa keteraturan dan arti pada semua fenomena.
Karena jika tidak demikian, maka teori akan tetap dianggap tidak masuk akal.1
Pokok permasalahan yang ditimbulkan oleh teori ini menyangkut hakikat dari politik.
Sejarah dari pemikiran politik modern adalah sebuah kisah perlombaan antara dua
golongan yang memiliki perbedaan konsepsi mengenai hakikat manusia, masyarakat, dan
politik. Golongan pertama percaya bahwa rasional politik dan moral politik yang berasal
dari prinsip-prinsip abstrak yang berlaku secara universal dapat dicapai saat itu juga.
Golongan ini juga percaya bahwa pendidikan, pembaharuan, dan penggunaan kekuatan
yang sporadis bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam tatanan sosial. Golongan
lain percaya bahwa jika dunia dilihat dari sudut pandang rasional dengan keadaannya
yang tidak sempurna, merupakan hasil dari sumber daya yang sudah inheren dari hakikat
manusia.untuk memperbaiki dunia, kita harus bekerja dengan sumber daya yang sudah
ada, dan tidak merusaknya.2
Realis menyadari bahwa keinginan manusia itu besar dan beragam, mereka
mengedepankan aspek keegosisan dan aspek dasar manusia lainnya untuk melakukan
diplomasi. Sebagaimana Machiavelli mengatakan jika dalam politik kita harus
berperilaku seolah-olah semua manusia adalah jahat dan mereka akan melakukan hal
jahat tersebut jika ada kesempatan. Pride, lust, dan the quest of glory merupakan salah
satu faktor yang menyebabkan terjadinya perang antarsesama. Sehingga dapat
disimpulkan akar dari konflik dan perang adalah dari sifat manusia.3
1 Hans J. Morghentau, Politics Among Nation, 6
thed., New York: McGraw Hill, 1985 hlm. 3-4
2 Ibid.
3 Ja k Do elly, Realis i “ ott Bur hill et all eds , Theories of I ter atio al Realtions, London: Palgrave
2005 hlm. 31
B. History
The Peloponnesian War (Perang Peloponnesian)
Dalam buku Thucydides yang berjudul The History of Peloponnesian War,
disebutkan bahwa Perang Peloponnesian terjadi antara Kerajaan Athena dengan Sparta
pada 431 SM. Perang antara Athena dan Sparta bermula dari sikap Sparta yang merasa
terancam karena Athena tengah mengembangkan kekuatan militernya, sehingga dalam
kasus ini menimbulkan security dilemma4. Ditambah lagi, imperialisme yang dilakukan
Athena terhadap Pulau Melos yang masih masuk kedalam kelompok Lakedaemon
semakin membuat keamanan Sparta terancam.
“The growth of the power of Athens, and the alarm which this inspired in
Lacedaemon, made war inevitable”5
Sebelum perang tersebut terjadi, gencatan senjata dilakukan antara Athena dan juga
Sparta pada tahun 421 SM. Akan tetapi, gencatan senjata yang dilakukan oleh keduanya
tidak menunjukkan hasil yang memuaskan, sehingga meletuslah kembali perang kedua
kerajaan tersebut pada tahun 431 SM dengan penyerangan yang diawali oleh Sparta
terhadap Athena. Kata kunci berupa power menjadi hal utama yang patut diperhatikan
dalam menganalisis peristiwa peperangan ini. Power yang ditunjukkan oleh Kerajaan
Athena dengan cara melakukan imperialisme dan juga mengembangkan kekuatan
militernya, hal itu memperlihatkan bahwa pengaruh realisme klasik sekiranya sudah
mulai berkembang sejak zaman Yunani kuno. Kekuatan yang mereka kembangkan
didasari atas satu kepentingan tertentu atau memiliki interest tertentu. Dalam hal ini,
dapat dipahami bahwa power memiliki kaitan yang erat dengan interest. Dengan kata
lain, setiap aktor negara akan selalu berusaha mencapai interest-nya termasuk dengan
cara menggunakan power yang dimiliki.
4Security dilemma adalah satu keadaan dimana terciptanya rasa tidak aman ketika suatu negara mengembangkan
kekuatan militernya dan dianggap mengancam keamanan negara yang lain. 5 Thucydides, The History of Peloponnesian War, Book 1
The Melians Dialogue
The Melians merupakan nama lain dari penduduk Pulau Melos yang terletak di
sebelah tenggara laut Aegean, dan tepatnya berada di sebelah timur dari Kerajaan Sparta.
Pulau Melos merupakan salah satu pulau yang menjadi target imperialisme Kerajaan
Athena. Imperialisme yang dilakukan oleh kerajaan Athena terhadap penduduk Melians di
dasari oleh beberapa hal. Salah satunya adalah karena kerajaan Athena ingin menambah
armada pasukan militernya dengan mengajak penduduk Melians untuk bergabung di
dalamnya. Akan tetapi, penduduk Melians menolak ajakan tersebut karena mereka
memiliki argumen yang menyatakan bahwa:
a) Mereka merupakan sebuah negara kota atau city state yang tidak memihak
kepada siapapun atau bersikap netral serta tidak memiliki musuh. Sehingga
Athena tidak berhak untuk menghancurkan mereka.
b) Melians beranggapan invasi yang dilakukan oleh Athena akan memberi
peringatan terhadap negara-negara kota lainnya di Yunani yang bersikap netral
dan akan membuat negara-negara kota tersebut memusuhi Athena.
c) Perang tidak akan membuat suatu pernyataan bahwa negara tersebut lemah dan
pengecut, melainkan masih ada cara lain selain berperang.
Akan tetapi, argumen yang disampaikan oleh Melians tidak dihiraukan oleh Athena,
sehingga Athena tetap menjalankan invasinya dan Melians pun takluk akan serangan
Athena.
Pericles’ Funeral Oration
Pericles, merupakan salah satu pemimpin Athena pada periode sekitar 461 – 429 SM6.
Pada masa kepemimpinannya, Pericles menjalankan satu perangkat konstitusi dalam
bernegara. Jika pandangan sebelumnya realisme sangat diperlihatkan di Athena, maka
pada masa kepemimpinan Pericles pandangan mengenai demokrasi mulai terlihat. Dengan
kata lain, sentuhan paham liberalisme mulai masuk ke Athena. Pada masa
kepemimpinannya, konstitusi dianggap Pericles dapat berperan penting dalam mengatur
kehidupan agar lebih baik.
Dalam pidatonya yang dilakukan pada upacara pemakaman korban peperangan antara
pasukan Athena dan Sparta, Pericles mengutarakan kebijakan politik dan juga program-
programnya mengenai upaya Athena agar dapat bertarung dalam peperangan dengan baik.
Pericles mengajak masyarakat Athena untuk konsentrasi dalam bidang kelautan, dengan
6 Thucydides, The History of Peloponnesian War, Pericles’ Funeral Oration
menguasai kelautan diharapkan menjadi satu kekuatan tersendiri ketika berhadapan
dengan Sparta.7 Pidato kedua yang disampaikan oleh Pericles lebih diarahkan kepada
upaya yang akan dilakukan pada akhir tahun pertama perang, yaitu dengan banyak
melakukan kerjasama dengan negara lain, terutama dalam bidang perdagangan. Secara
tidak langsung apa yang disampaikan oleh Pericles merupakan salah satu wujud
pemahaman akan liberalisme melalui konsep demokrasi, karena menurut Pericles, dengan
melakukan banyak kerjasama dan mampu mendominasi setiap bidang, kekuatan Athena
secara perlahan namun pasti akan semakin besar. Konstitusi seperti yang disampaikan oleh
Pericles, nantinya bukan hanya mampu mengatur kehidupan rakyatnya, tetapi juga dapat
melindungi pemimpin. Ditambah lagi dalam demokrasi, hal yang harus ada didalamnya
adalah masalah etika dan moral. Tanpa keduanya, demokrasi hanya akan menjadi alat
pemenuhan kepentingan sekelompok orang.
7 Thucydides, The History of Peloponnesian War, Pericles’ Funeral Oration
C. Classical Realism Perspective
Hobbes membuat tiga asumsi singkat mengenai realisme klasik, yaitu:8
1. Manusia adalah sederajat.
Hobbes mengatakan, the weakest has strength enough to kill the strongest, either by
secret machination or by confederacy with others. Dapat diartikan jika semua manusia
memiliki kesempatan yang sama dalam meraih semua mimpinya. Tapi kemudian
kelangkaan menyebabkan manusia memiliki keterbatasan dalam meraih semua hal, yang
kemudian hal inilah yang menyebabkan terjadinya permusuhan diantara mereka.
2. Mereka berinteraksi dalam anarki.
Sejak tidak ada pemerintahan tertinggi yang dapat menjamin keamanan satu dengan
yang lainnya, mereka semua berada dalam kondisi yang disebut dengan perang.
Kemudian muncul asumsi jika peperangan ini dapat dicegah dengan adanya kekuatan
yang mengimbangi kekuatan lainnya. Membangun pemerintahan internasional mungkin
dapat mengakhiri peperangan antar negara.
3. Mereka dikendalikan oleh kompetisi, ketidakberanian, dan kemenangan.
Dari asumsi dasar ini dapat disimpulkan jika aktor yang sama saling berinteraksi
dalam anarki yang dikendalikan oleh kompetisi, ketidakberanian, dan kemuliaan, konflik
kekerasan dapat diprediksi akan terjadi. Seperti kebanyakan realis lainnya, Hobbes
merasa ragu atau skeptis bahwa sifat dasar manusia dapar diubah. Tapi, kita dapat
menyetujui asumsi Hobbes tentang tekanan dalam kompetisi, ketidakberanian dan
kemuliaan mewakili sebuah pertimbangan yang serius.
Tapi kemudian anarki telah digantikan oleh peraturan politik secara hierarki.
Pemerintahan yang jahat dan kurang efisien pun dengan sungguh-sungguh menyediakan
keamanan untuk melindungi penduduk dan properti mereka. Hal ini dilakukan untuk
mengurangi tekanan untuk menggantikan pemerintahan yang alami (seharusnya) dengan
pemerintah internasional.9
E.H. Carr dalam bukunya membagi realisme ke dalam ranah pemikiran dan ranah
praktek. Ranah pemikiran realisme lebih menekankan pada penerimaan fakta dan analisis
atas sebab dan dampaknya. Sedangkan, ranah praktek realisme lebih memperhatikan
8 Ja k Do elly, Realis i “ ott Bur hill et all eds , Theories of I ter atio al Realtio s, London: Palgrave,
2005 hlm. 32 9 Ja k Do elly, Realis i “ ott Bur hill et all eds , Theories of I ter ational Realtions, London: Palgrave,
2005 hlm. 34
kekuatan alamiah maupun karakter alamiah yang membuat kebijaksanaan tertinggi di
pegang oleh dua kecenderungan tersebut.10
Sedangkan Gilpin (1986:305) mengemukakan bahwa terdapat dua penekanan
utama pada perspektif realis. Pertama, adanya pemaksaan politis yang didasari oleh
egoisme manusia. Kedua, yaitu tidak adanya pemerintahan internasional yang
menyebabkan anarki, sehingga kemudian membutuhkan keunggulan power dan
keamanan.11
Six Principles of Political Realism According to Morgenthau12
Asumsi dasar dari Thomas Hobbes ini kemudian dikembangkan oleh salah satu
tokoh realis yang terkenal yaitu Morgenthau. Dia kemudian mengembangkan menjadi
enam prinsip realis, yaitu:
1. Politik dikendalikan oleh hukum objektif yang berakar pada hakikat manusia.
Untuk memperbaiki masyarakat, terlebih dahulu haruslah memahami hukum
yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Realisme percaya pada hukum
objektivitas politik, juga percaya terhadap kemungkinan untuk mengembangkan teori
rasional yang mencerminkan hukum objektif, meskipun hukum objektif tersebut bisa
dikatakan memihak/tidak seimbang.
Realisme juga percaya akan kemungkinan politik dalam membedakan antara
kebenaran yang memang benar secara rasional dan objektif, juga didukung oleh bukti
dan diperjelas dengan alasan, dan opini yang dinilai secara subjektif, tidak sama dengan
fakta, dan diperkuat oleh dugaan-dugaan serta hayalan/imajinasi belaka.
2. Konsep “kepentingan/interest” yang didefinisikan dan diperjuangkan melalui
kekuasaan/power.
Konsep kepentingan yang didefinisikan sebagai kekuasaan, memaksakan sebuah
disiplin intelektual kepada para pengamat untuk memasukkan tatanan rasional kedalam
pokok permasalahan politik, sehingga membuat pemahaman politik secara teoritis. Bagi
para aktor, konsep tersebut memberikan sebuah disiplin yang rasional dalam mengambil
tindakan dan menimbulkan kontinuitas yang mengejutkan terhadap kebijakan luar negeri
Amerika, Inggris dan Rusia (sebagai contoh) yang muncul secara jelas dan sebagai
kesatuan yang rasional. Jadi, pandangan Realis terhadap politik internasional akan
10
Scott Burchill, Andrew Linklater, Teori-teori Hubungan Internasional, Bandung: Nusamedia, 2009, hlm. 92 11
Ja k Do elly, Realis i “ ott Bur hill et all eds , Theories of I ter atio al Realtio s, Lo do : Palgra e, 2005 hlm. 30 12
Hans J. Morghentau, Politics Among Nation, 6th
ed., New York: McGraw Hill, 1985 hlm. 4-14
berhati-hati terhadap dua buah kesalahpahaman, yakni yang berkenaan dengan motif dan
preferensi ideologis.
Penting untuk kita ketahui jika kita ingin memahami politik luar negeri, yang
harus kita pahami bukan motif negarawan yang mempraktikan politik luar negeri
tersebut, melainkan harus memahami kemampuan intelektual negarawan tersebut dalam
memahami permasalahan-permasalahan politik luar negeri yang dihadapi, agar tindakan
yang dia (negarawan) ambil dalam menentukan politik luar negeri bisa berhasil.
Sudah menjadi kebiasaan jika politik luar negeri tidak selalu rasional, objektif,
dan tidak emosional. Unsur-unsur seperti kepribadian, dugaan, subjektivitas, dan semua
kelemahan intelektual pasti akan membelokkan arah politik luar negeri keluar dari
rasionalitas. Terlebih jika suatu negara menganut sistem demokrasi, maka negarawan
harus berjuang dalam mendapatkan dukungan dari rakyat untuk mendukung politik luar
negeri yang telah dibuatnya.
Perbedaan antara politik internasional yang sesungguhnya dengan teori rasional
bisa dianalogikan seperti foto hasil kamera dan foto hasil lukisan. Foto hasil kamera
dapat menunjukkan segala sesuatu bisa dilihat oleh mata, sedangkan foto hasil lukisan
tidak dapat menunjukkan segalanya yang dapat dilihat oleh mata. Hal ini menunjukkan
bahwa ada satu hal yang tidak bisa dilihat oleh mata dalam dunia politik internasional
yakni sifat alamiah manusia yang digambarkan oleh seseorang.
Realisme politik tidak hanya memuat unsur-unsur teoritis, tetapi juga unsur-unsur
normatif. Realis berasumsi bahwa realitas politik penuh dengan ketidakpastian dan
keadaan yang tidak masuk akal dan sistemik, serta berpengaruh terhadap pengambilan
kebijakan luar negeri. Realisme juga menganggap bahwa politik luar negeri yang
rasional merupakan politik luar negeri yang baik. Karena, hanya politik luar negeri yang
rasional-lah yang mampu memperkecil resiko dan meningkatkan keuntungan sebanyak
mungkin.
3. Kepentingan bersifat dinamis, objektif dan berlaku secara universal.
Corak kepentingan yang menentukan tindakan politik suatu negara dalam periode
tertentu, dapat dilihat dari konteks politik dan kebudayaan. Dalam konteks ini, sasaran
yang mungkin ingin diraih oleh setiap negara dalam politik luar negerinya dapat meliputi
seluruh rangkaian tujuan yang mungkin pernah menjadi tujuan yang harus dicapai oleh
negara lain, atau bahkan yang masih harus dicapai oleh negara lain.
Kepentingan itu sendiri bersifat dinamis, artinya kepentingan selalu bergerak
sesuai dengan keadaan politik internasional. Setiap negara memiliki kepentingan yang
berbeda-beda, tergantung dari sistem pemerintahan, dan motif yang mempengaruhi
negarawan dalam mengambil kebijakan luar negeri.
4. Realisme sadar akan signifikansi moral dari tindakan politik.
Realisme politik menyadari pentingnya moral dari tindakan politik bagi individu,
tetapi hal itu tidak dapat diimplementasikan kedalam tindakan-tindakan negara dalam
mengambil keputusan politik luar negeri. Ketika individu dapat berkata “Fiat justitia,
pereat mundus” (biarkan keadilan berlaku, sekalipun dunia binasa), lain halnya dengan
negara. Negara tidak berhak untuk berkata seperti itu, sekalipun atas nama mereka yang
berlindung terhadap negara tersebut. Lalu, realisme juga menganggap bahwa
kebijaksanaan (pertimbangan atas konsekuensi alternative tindakan politis) sebagai
kebaikan tertinggi dalam politik.
5. Prinsip moral universal harus dikesampingkan jika bertentangan dengan
national interest. Karena tujuan negara adalah survive dengan cara
memperjuangkan national interest.
Semua negara ingin menutupi kepentingan dan tindakan khusus mereka dalam
tujuan moral universal. Untuk mengetahui bahwa negara adalah subjek dari hukum moral
universal adalah suatu hal yang penting, sedangkan untuk mengetahui secara pasti mana
yang baik dan mana yang jahat dalam hubungan antar bangsa adalah hal lain.
Konsep kepentingan yang didefinisikan kedalam kekuasaan telah menyelamatkan
kita dari kebodohan politik itu sendiri. Jika kita bercermin terhadap negara lain sebagai
wujud politik yang mengejar kepentingan mereka masing-masing yang juga
didefinisikan dengan istilah kekuasaan, maka kita dapat memperlakukan semua itu
dengan adil. Dengan begitu, maka kita bisa berbuat adil dalam arti ganda, yakni, kita bisa
menilai bangsa-bangsa lain seperti halnya kita menilai bangsa kita sendiri, dan setelah
menilai dengan gaya ini, maka kita akan mampu menghormati kepentingan negara lain
selagi kita mampu menjaga dan mempromosikan kepentingan kita sendiri.
6. Perbedaan realisme politik dengan paradigma lain.
Kajian yang dilakukan oleh realism politik terbukti lebih nyata karena realisme
berusaha mengkaji apa yang benar-benar terjadi di dunia internasional. Kajian yang
dilakukan-pun mendalam dan menyeluruh. Namun, banyak dari asumsi-asumsi teori
realism politik yang disalahartikan dan disalahtafsirkan. Meski begitu, tidak ada yang
bisa menyangkal sikap intelektual dan moral kaum realis terhadap masalah yang bersifat
politis.
Kaum realis cenderung mempertahankan otonomi di bidang politik, namun tetap
mengakui eksistensi dan pentingnya pemikiran-pemikiran di bidang lain (selain politik).
Namun, hal itu harus ditempatkan sesuai dengan dunia dan fungsinya, karena realism
politik didasarkan pada hakikat manusia yang pluralistik dimana manusia itu sendiri
merupakan gabungan atas “economic man”, “political man”, “moral man”, “religious
man”, dan lain-lain. Seseorang yang hanya merupakan “political man” akan menjadi
hewan buas, karena ia sama sekali tidak memiliki kendala moral. Dengan mengakui
perbedaan-perbedaan dari hakikat manusia, kaum realis juga berpendapat supaya bisa
memahami salah satu sifat tersebut, maka kita harus memahaminya dengan caranya
sendiri. Missal saya ingin memahami “religious man” maka saya harus menjadi orang
religious dengan cara mengesampingkan hal duniawi. Maka menurut Morgenthau,
”political man” adalah sifat yang paling cocok untuk meneliti manusia dalam bidang
politik, karena menurutnya manusia hanya tertarik pada kekuasaan.
Dari beberapa asumsi yang sudah diberikan oleh tokoh-tokoh realisme diatas,
dapat ditarik kesimpulan, jika asumsi dasar realisme adalah:
- Pandangan pesimistis atas sifat dasar manusia.
- Keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konfliktual dan bahwa
konflik internasional pada akhirnya diselesaikan melalui perang.
- Menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara.
- Skeptisme dasar bahwa kemajuan dalam politik internasional bisa sama dengan
politik domestic
- Sifat alami manusia adalah egois.
- Negara adalah aktor utama. Jadi, hubungan internasional mempelajari bagaimana
negara berinteraksi dengan yang lainnya.
- Motivasi negara adalah kepentingan nasional. Dalam mencapai hal itu digunakan
kebijakan luar negeri.
- Kekuasaan (power) adalah kunci untuk memahami perilaku internasional dan motif
suatu negara.
D. The Concept of Power and Interest
Kaum utopia-liberal hendak menghilangkan kekuasaan sebagai pertimbangan negara
dalam sistem internasional. Carr percaya bahwa usaha negara dalam pemenuhan
kepentingan negaranya merupakan dorongan alami yang jikalau hal tersebut dihindari
dan tidak dilakukan oleh negara maka akan membahayakan negaranya sendiri. Pencarian
kepentingan nasional oleh negara dipahami oleh realis sebagai sebuah kekuatan
strategis.13
Kaum realist memberikan defenisi terkait kepentingan yakni sebagai bagian dari
bentuk kekuasaan. Kebanyakan kaum realis mempercayai keunggulan kepentingan diri
sendiri diatas prinsip moral, dan menganggap pertimbangan keadilan tidaklah tepat jika
hal tersebut tidak membahayakan pondasi yang merupakan dasar dari kebijakan luar
negri. Realis menganggap bahwa seruan akan keadilan bisa berguna untuk membenarkan
atau melindung alasan kebijakan demi memenuhi suatu kepentingan materi yang lebih
nyata.
Para realis klasik menganggap kekuasaan adalah sebagai satu – satunya sumber
kekuasaan. Selain itu mereka tidak ingin menyamakan antara kekuasaan dengan
pengaruh. Bagi mereka, pengaruh adalah hubungan psikologi dan seperti halnya semua
hubungan yang lainnya semua berdasarkan keeratan yang melebihi kepentingan sesaat.
Keadilan tentu mengambil peran nya dalam hal ini. Keadilan merupakan dasar dari suatu
hubungan dan pengertian atas sebuah komunitas dimana mereka bergantung pada
pengaruh dan keamanan.
Awalnya, Thucydides mengatakan bahwa sejarah menggambarkan suatu ketegangan
antara kepentingan dan keadilan serta bagaimana hal itu menjadi lebih tajam dalam
merespon akan desakan perang. Ia juga menyatakan bagaimana kepentingan dan
keadilan adalah dua hal yang tidak terpisahkan dan saling menyokong pada tingkat yang
lebih lanjut. Keadilan atau setidaknya percaya akan keadilan adalah pondasi utama bagi
sebuah komunitas. Pengertian tentang kepentingan diluar bahasa keadilan adalah sesuatu
yang tidak masuk akal dan akan merugikan diri mereka sendiri.14
Dalam chapter X (Of Power, Worth, Dignity, Honour and Worthiness), Hobbes
mengklasifikasikan power kedalam dua jenis: Natural Power dan Instrumental Power.
Natural Power berasal dari kemampuan badan atau fikiran. Natural Power juga
13
Scott Burchill, Andrew Linklater, Teori-teori Hubungan Internasional, Bandung: Nusamedia, 2009, hlm. 95 14
Ri hard Ned Le o , Classi al Realis , i Ti Du e et al eds , I ter atio al Relations Theory: Discipline
and Diversity, UK: Oxford University Press, 2012.
merupakan power yang secara alami ada dalam diri manusia, seperti kekuatan, akal, dan
lain-lain. Kemudian, Instrumental Power berasal dari kemampuan yang diperoleh dari
hasil usaha manusia, seperti popularitas seseorang yang meningkat seiring dengan proses
atau usaha yang dilakukan oleh orang tersebut.
Morgenthau sendiri mendefiniskan power sebagai pengendalian pikiran maupun
perilaku dari yang lainnya. Yang kemudian kapasitas power dibagi lagi menjadi:15
- Geography: Natural barriers, large amounts of buffer territory, etc.
- Natural Resources: Food self-sufficiency capacity, energy resources, military materiel
resources
- Industrial capacity: Enables military competitiveness, economic stability
- Population: Strength in numbers
- Military Preparedness (short term): Numbers, capabilities, training
- National Character/Morale: Resiliency, military ethos, patriotism, etc.
International politics is about the struggle for power. Ketika kita berbicara mengenai
power, maka yang dimaksud adalah kontrol seseorang atas pikiran tindakan orang lain.
Sebagai contoh, A memiliki kekuatan politik atas B, sejauh A mampu mengendalikan
tindakan B dengan cara mempengaruhi pikiran B.
Menurunnya nilai kekuatan politik
Menurunnya nilai kekuatan politik salah satunya disebabkan oleh “struggle for
power” (perebutan kekuasaan). Fenomena ini pertama kali muncul pada zaman
kolonialisasi. Pada zaman ini, para koloni berkompetisi untuk memperluas wilayah
kekuasaannya demi mencapai national interest masing-masing negara penjajah.16
Jeremy
Bentham17
percaya bahwa kompetisi dalam koloni tersebut adalah akar dari konflik
internasional
Lalu, bagaimana mengatasi hal tersebut?
- Marx dan pengikutnya percaya bahwa kapitalisme merupakan akar dari perpecahan
dan perang. Mereka mempertahankan paham yang mereka pegang bahwa sosialisme
internasional akan menciptakan kedamaian yang permanen.
- Memasuki abad ke-19, paham liberalisme mendominasi dunia internasional. Kaum
liberalis percaya bahwa kekuatan politik dan perang adalah sisa-sisa dari sistem
pemerintahan kuno. Mereka percaya bahwa kerukunan internasional dan perdamaian
abadi akan tercipta tanpa adanya kekuatan politik dan perang. Mereka yakin bahwa
15
Ha s J. Morge thau, Kekuata Nasio al , Politik A tar Ba gsa, edisi ke-6, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
Indonesia, 2010, hlm. 135-181. 16
Hans J. Morgenthau, Politic Among Nations, 4th
ed., New York: McGraw Hill, 1966, hlm. 16. 17
Jeremy Bentham adalah salah seorang filsuf empirisme dalam bidang moral dan politik asal Inggris.
struggle for power dapat dihilangkan darim dunia internasional, yakni dengan
dibentuknya PBB, sehingga bisa menjadi tempat bagi kerjasama internasional.
- Namun kaum realis percaya bahwa adanya struggle for power di dunia internasional
tidak dapat disangkal. Karena, pada faktanya, dalam segala kondisi (baik dalam
bidang ekonomi, sosial, politik), negara-negara di dunia bertemu untuk
memperjuangkan power. Menurut kaca mata realis, dibentuknya PBB bukan untuk
dijadikan sebagai aktor dalam hubungan internasional, melainkan suatu alat untuk
menjaga stabilitas balance of power. Karena, menurut kaum realis, perdamaian hanya
akan tercapai jika ada balance of power.
E. Critic of Classical Realism
Terdapat dua kritik dari para ahli yang lain mengenai Realisme Klasik, yaitu: 18
1. Critics argue that many states are too weak and ill formed to sustain the inside-
outside distinction. Somalia dan Rwanda are only the latest in a long line of examples
where the inside looks more like the outside is supposed to be.
2. Critics argue that the state is now so penetrated by transnasional actors and forces
that the inside-outside distinction has become a meaningless blur.
Sedangkan Nicholas Spykman mengklaim bahwa pencarian dari kekuasaan bukanlah
hanya sekadar untuk nilai-nilai moral, tapi nilai moral yang digunakan untuk pencapaian
kekuasaan tersebut.19
Kritik lainnya diungkapkan oleh Juanita Elias dan Peter Stuch dalam buku “The
Basics International Realations”, yaitu:20
- Pertama, adanya isu tentang kekuasaan (power) dan kepentingan nasional (national
interest) yang menjadi tujuan dari negara. Kedua hal ini membuat pemahaman kita
tentang politik internasional menjadi sangat sederhana. Politik internasional dapat
dijelaskan dalam konteks lainnya seperti sejarah.
- Kedua, bahwa sifat dasar manusia adalah penyebab konflik. Dalam sejarah, jelas
dikatakan bahwa manusia mampu bertindak secara bar-bar dan egois. Bagaimanapun,
hal ini telah dibangun sejak dahulu dan menjadi sebuah kebiasaan. Tapi tentu saja
dengan akal dan pertimbangan, kita dapat memilih untuk lebih mengedepankan
kerjasama daripada konflik, perasaan daripada kekejaman. Mungkin hal yang sulit
untuk dipilih tapi jika dilakukan sungguh-sungguh tentu akan membuat perbedaan
pandangan tentang hubungan internasional.
- Ketiga, negara merupakan aktor utama. Pemahaman negara sebagai aktor utama
adalah sebagai alat untuk menjaga eksistensi dan untuk bertahan (survival).
Kedaulatan negara merupakan masa depan untuk kemodernan dan menjawab
berbagai masalah. Tapi kemudian timbul permasalahan apakah kedaulatan negara
dapat menjawab permasalahan seperti negara yang pecah, hak-hak kaum minoritas,
yang dimana politik dibutuhkan untuk menanggapi permasalahan kemanusiaan, krisis
18
Smith, Booth, and Zalweski; International Theory: Positivism and Beyond; Cambridge University Press, 1996
hlm. 52 19
Ja k Do elly, Realis i “ ott Bur hill et all eds , Theories of I ter atio al Realtio s, Lo do : Palgra e 2005 hlm. 52 20
Jua ita Elias a d Peter “ut h, :The Basi s I ter atio al Relatio s , Ne York: Routledge 2007 hl . 59-61
pengungsi dan kemiskinan global. Yang menjadi pertanyan selanjutnya adalah
apakah eksistensi kedaulatan negara dapat bertahan atau harus mengikuti aturan
regional yang membuat kedaulatan itu sendiri menjadi bias?
- Keempat, adanya subordinasi moral dalam politik. Yang menjadi masalah adalah kita
dapat mentolerir nilai-nilai moral dalam pemenuhan kepentingan. Hal ini
mengindikasi bahwa para pemimpin dapat melakukan hal yang bertentangan dengan
moral hanya untuk pemenuhan kebutuhan negaranya. Salah satu konsep dalam realis
ini tentu saja bertentangan dengan Universal Declaration 1948.
- Kelima, substansi dari hubungan internsional adalah tentang persaingan negara,
perang, dan agresi. Adalah benar jika hal tersebut adalah salah satu kunci dari
hubungan internasional. Tetapi masih ada aspek lainnya yang tentu perlu dikaji.
Perspektif realis mendukung sebuah hal yang salah jika fokus utama mempelajari
hubungan internasional adalah untuk mempelajari keamanan (security) saja. Padahal
banyak yang dapat dikembangankan seperti ekonomi internasional atau hukum
internasional
Realis mungkin tidak sepenuhnya dapat menjawab fenomena-fenomena dalam
hubungan internasional. Anarki, keegoisan, dan kemampuan untuk pendistribusian tidak
dapat menjelaskan pelbagai bidang dalam hubungan yang luas.
F. Case Study with Classical Realism Perspective
Kompas – Lembaga hak asasi manusia (HAM) Internasional, Amnesty International,
menuding Pemerintah Suriah melakukan pelanggaran berat HAM. Tudingan lembaga
itu, merujuk pada blokade dan pembiaran kelaparan terhadap warga Yarmouk.
Catatan lembaga itu menunjukan bahwa 200 warga Yarmouk mati kelaparan dan
terkena penyakit. Kira-kira, ada 200.000 warga Yarmouk kala itu. Blokade
berlangsung setahun silam dan makin ketat lantaran pemerintah suriah menempatkan
pasukan loyalis rezim presiden Bashar Al-Assad. Amnesty International mengatakan
dari 200 warga Yarmouk yang tewas itu 128 diantaranya mati kelaparan.
Republika – Amerika mulai mencari cara untuk mengintervensi Suriah. Disitu
Amerika membahas langkah-langkah untuk membantu oposisi Suriah yang moderat.
Pilihan bantuan yang akan diberikan adalah bantuan kemanusiaan, mendirikan zona
aman di wilayah Suriah mungkin melalui cara-cara militer.
Analisis:
Berdasarkan prinsip-prinsip Realis, intervensi yang dilakukan Amerika ke Suriah
adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Pandangan ini dapat terlihat jika meninjau
dari asumsi dasar mengenai realis yakni :
1. Negara adalah aktor dan unit analisis utama dalam studi HI. Aktor-aktor non-negara
dipandang kurang penting dibandingkan negara. Dengan demikian, realisme bersifat
state-centric dan berfokus pada hubungan antar negara.
2. Negara adalah aktor yang tunggal (unitary) di mana seluruh perbedaan di dalam
negara dianggap sudah selesai dan negara memiliki satu suara resmi.
3. Negara adalah aktor yang rasional dalam artian mengejar tujuan-tujuannya dengan
mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan kapabilitas yang dimilikinya.
4. Politik internasional dikarakteristik kan oleh pengejaran power dan power politics di
antara negara-negara sehingga isu keamanan (high politics) menempati prioritas
tertinggi dalam agenda negara.
Jika kita cermati kasus yang terjadi pada konflik di Suriah pada dasarnya adalah
konflik internal yang terjadi antara pemerintahan rezim Bashar al-assad melawan
pemberontak (oposisi). Dalam hal ini rezim al-assad dibantu oleh Rusia dan China.
Bahkan senjata pemusnah massal justru digunakan untuk menghabisi para pemberontak
yang notabane nya adalah rakyatnya sendiri.
Berangkat dari isu ini setidaknya ada beberapa hal yang menarik perhatian Amerika
untuk melakukan intervensi di Suriah. Pertama, karena adanya peran Rusia. Sudah
menjadi rahasia umum di dunia internasional bahwa Rusia adalah musuh bebuyutan dari
Amerika Serikat, menyadari akan peran Rusia dalam konflik Suriah maka Amerika ikut
melibatkan diri dengan membantu para pemberontak Suriah. Dalam hal ini jelas kita lihat
bahwa ada upaya untuk melakukan balance of power yang dilakukan AS. Dalam
perspektif realis melihat Rusia sebagai salah satu kekuatan terbesar di dunia maka perlu
dibendung agar tidak semena-mena menguasai dunia.
Faktor kedua yang menyebabkan intervensi Amerika adalah aksi menghabisi rakyat
yang dianggap pemberontak yang dilakuakan oleh rezim al-asad. Amerika menilai apa
yang telah dilakukan oleh rezim al-assad ini adalah suatu tindak kejahatan HAM yang luar
biasa. Inilah yang kemudian dikalangan liberalis dikenal dengan istilah humanitarian
intervention. Sejak berakhirnya perang dingin, dunia berubah dengan cepat. Dengan
kolapsnya Uni Soviet yang memainkan perang vital sepanjang 4 dekade perang dingin
berimplikasi luas terhadap tatanan politik dunia setelah itu. Ide kedaulatan absolut
dianggap tidak lagi relevan apabila peran negara sangat minim dalam melindungi
rakyatnya. Terlebih apabila keberadaan negara mengancam kelangsungan hidup
warganya.
Dalam perspektif realis, apa yang telah dilakukan oleh rezim al-assad dapat
dibenarkan karena untuk mempertahankan kekuasaanya. Hal ini didasarkan pada konsep 3
S yang diterapkan oleh realis, yakni Survival, Statism, Self help. Alasan Humanitarian
intervention juga tidak dapat dibenarkan dalam realis, karena mereka berkeyakinan bahwa
mereka dapat menyelesaikan konflik internalnya sendiri tanpa campur tangan asing.
Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Mearsheimer, Perang di Timur Tengah
sesungguhnya terjadi akibat paham idealisme: keinginan untuk menciptakan dunia yang
demokratis. Mearsheimer menggunakan istilah ‘Wilsonianism with teeth’. Wilsonian
adalah sebutan bagi pemikiran Woodrow Wilson, Presiden AS ke 28 yang pada tahun
1918 menyampaikan pidato monumentalnya “14 Points”. Wilson mengatakan, “Dunia
harus dibuat aman bagi demokrasi. Menarik jika dicermati lebih lanjut bahwa intervensi
Amerika juga dikarenakan penolakan Suriah terhadap sistem Demokrasi.
Padahal kaum realis lebih percaya bahwa kita hidup di dunia yang menyeimbangkan
(balancing world). Artinya, saat sebuah negara mengepalkan tinju di hadapan negara lain,
negara lain itu tidak akan mengangkat tangan dan menyerah begitu saja. Negara itu pasti
akan mencari jalan untuk mempertahankan diri sendiri; dia akan menyeimbangkan diri di
hadapan negara pengancam. Sehingga demokratisasi sebetulnya tidak perlu ditetapkan.
Kesimpulan
Dalam perspektif Realis menilai bahwa penyerangan AS ke suriah merupakan bentuk
intervensi karena adanya national interest yang diperjuangkan oleh Amerika, seperti
demokratisasi di Suriah, dalam kasus ini AS juga khawatir jika hegemoninya terancam
oleh Cina, karena seperti yang kita tahu Cina sudah mulai berada sejajar untuk menyaingi
amerika. Adanya keterlbatan Rusia juga menjadi faktor mengapa AS mengintervensi
Suriah.
Mereka bahkan menilai bahwa intervensi harus dilakukan karena alasan humanitarian
intervention, AS menganggap Suriah tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai pelindung
rakyat, dalam hal ini perlindungan HAM, seperti yang tertulis pada konsep RTP
(Responsibility to Protect) pada tahun 2001, diperkenalkan oleh International Cmmission
on Intervention and State Sovereignity) Pandangan-pandangan yang concern terhadap isu
HAM adalah pemahaman kalangan liberalis yang kita ketahui bertentangan dengan paham
Realis.
Sumber Referensi:
- Burchill, Scott and Andrew Linklater, Teori-teori Hubungan Internasional, Bandung:
Nusamedia, 2009.
- Donnely, Jack 2005 “Realism”, in Scott Burchill et all (eds), Theories of
International Relations, London: Palgrave.
- Elias, Juanita and Peter Sutch, The Basics: International Relations, New York:
Routledge, 2007.
- Lebow, Richard Ned 2012, “Classical Realism”, in Tim Dunne et al (eds),
International Relations Theory: Discipline and Diversity, UK: Oxford University
Press.
- Morgenthau, Hans J., Politics Among Nations, 6th
ed., New York: McGraw Hill,
1985.
- Morgenthau, Hans J., “Kekuatan Nasional”, Politik Antar Bangsa, edisi ke-6, Jakarta:
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Smith, Booth, and Zalweski, International Theory: Positivism and Beyond;
Cambridge University Press, 1996
- Thucydides, “The Melian Dialogue”, History of The Peloponesian War,
Hardmondsworth: Penguin Classics, 1954.