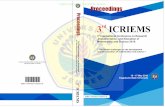The Local Adaptation Behavior in Forest Carbon Conservation Following the DA REDD+ Implementation in...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of The Local Adaptation Behavior in Forest Carbon Conservation Following the DA REDD+ Implementation in...
PERILAKU ADAPTASI KOMUNITAS LOKAL
DALAM UPAYA KONSERVASI KARBON HUTAN PASCA DA REDD+
DI KAWASAN TAMAN NASIONAL MERU BETIRI
KABUPATEN JEMBER
Novita Rini Wardani, Sofyan Cholid
1. Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Indonesia
2. Dosen Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Indonesia
E-mail : [email protected]
Abstrak
Penelitian ini membahas tentang perilaku adaptasi komunitas lokal di 3 (tiga) desa penyangga kawasan
Taman Nasional Meru Betiri setelah kegiatan DA REDD+ yang difokuskan pada dampak perilaku adaptif dan
aksi adaptasi. Pendekatan penelitian mempergunakan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil menunjukkan
bahwa adanya intervensi sosial pada Desa Curahnongko dan Andongrejo melalui program pemberdayaan
masyarakat yang dilakukan oleh LSM lokal mampu meningkatkan perilaku adaptif dan aksi adaptasi komunitas
lokal dalam upaya konservasi karbon hutan. Berbeda dengan Desa Wonoasri yang tidak mendapat intervensi
sosial dari LSM lokal yang kegiatan pemberdayaan masyarakatnya tidak berjalan optimal.
The Local Adaptation Behavior in Forest Carbon Conservation
Following the DA REDD+ Implementation in Meru Betiri National Park
District of Jember
Abstract
This research is to describe the local adaption behavior in 3 (three) villages buffering in Meru Betiri
National Park following the DA REDD+ implementation which is concern on adaptive behavior impact and
adaptation action. This research uses a qualitative approach with descriptive type. The result shows the
effectiveness of social intervention by local NGO in Curahnongko and Andongrejo through the community
development program can empower the adaptive behavior and local adaptation action to the forest carbon
conservation. Different with Wonoasri which has no social intervention through the community development
program from the local NGO not optimal implemented.
Keywords : Adaptive Behaviour, Adaptation, DA REDD+, Conservation, Social Intervention
A. Pendahuluan
Globalisasi dan liberalisasi pasar telah menjadikan hutan sebagai komoditas strategis
dalam investasi global yang membawa dampak pada meningkatnya laju deforestasi dan
degradasi hutan tropis di Indonesia. Menurut Data World Resources Institute (WRI) pada
tahun 2003 menunjukkan bahwa deforestasi berkontribusi sekitar 18% emisi global, 75% nya
berada di negara berkembang, dan diperkirakan akan terus meningkat bila tidak ada
intervensi kebijakan baik nasional maupun internasional (Masripatin, 2012). Hal ini berkaitan
2
erat dengan posisi negara Indonesia yang berada dalam tahap pertumbuhan ekonomi
(economic growth) yang cukup signifikan. Sehingga hutan menjadi salah satu sumberdaya
potensial yang dapat menjamin keberlangsungan perekonomian untuk terus maju, tumbuh
dan berkembang. Di sisi lain, keberadaan hutan memiliki peran penting terutama dalam
menjaga kestabilan iklim dunia. Sejumlah klaim menyebutkan bahwa terjadinya perubahan
iklim akibat pemanasan global, salah satunya dipicu oleh tingginya emisi CO2 akibat
deforestasi dan degradasi hutan.
Sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap upaya mitigasi perubahan iklim global
dan pengurangan emisi CO2, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor
61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Efek Gas Rumah Kaca. Salah
satu agenda pemerintah sebagai wujud kontribusi aktif dan komitmen untuk mengurangi
emisi karbon adalah dengan menunjuk kawasan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB)
sebagai Pilot ProjectDemonstration Activity (DA) REDD+ khususnya untuk kawasan hutan
konservasi di Pulau Jawa. Kegiatan DA REDD+ menjadi komponen penting dalam
menciptakan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat khususnya terkait dengan strategi
Readiness Phase di Indonesia.
Kegiatan DA REDD+ melalui “Konservasi Hutan Tropis untuk Pengurangan Emisi dari
Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Peningkatan Stok Karbon” di TNMB merupakan
kegiatan potensial di wilayah Pulau Jawa. Sejak ditetapkannya status Meru Betiri sebagai
Kawasan Taman Nasional melalui diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan
No.277/Kpts/DJ-V/1997 tanggal 23 Mei 1997, berarti bahwa pengelolaan kawasan Taman
Nasional Meru Betiri diarahkan pada fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan,
pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa beserta ekosistemnya serta
pemanfaatannya secara lestari. Namun, hal ini cenderung kontradiktif mengingat keberadaan
komunitas lokal yang telah lama mendiami wilayah desa penyangga dan menggantungkan
sebagian mata pencahariannya pada hasil hutan kayu dan non kayu.
Sebelum kegiatan DA REDD+ berlangsung Tahun 2010-2013, kajian analisis terhadap
kegiatan deforestasi dan degradasi hutan menjadi latar belakang yang mendasari kegiatan DA
REDD+. Laju deforestasi berdasarkan hasil analisis data penginderaan jauh Tahun 1997-2010
terhadap perubahan penggunaan lahan TNMB, menunjukkan laju deforestasi cukup rendah
dengan rata-rata per tahunnya mencapai 0,065%. Lain halnya dengan degradasi hutan yang
tinggi disebabkan oleh illegal logging masih saja sering terjadi khususnya di kawasan zona
rimba. Pelakunya adalah kelompok masyarakat yang tinggal disekitar desa penyangga
maupun di luar desa penyangga yang kurang memiliki kesadaran dan kepedulian rendah
terhadap kelestarian hutan.
3
Kegiatan DA REDD+ dikembangkan sebagai salah satu bentuk intervensi dalam upaya
perlindungan hutan TNMB sebagai kawasan konservasi, dimana dalam pelaksanaannya
melibatkan multistakeholder dengan harapan bahwa semakin beragamnya komponen
masyarakat yang terlibat, maka semakin besar efek positif yang akan diperoleh dari rangkaian
kegiatan DA REDD+ maka upaya mewujudkan kelestarian kawasan hutan TNMB dapat
berhasil dengan baik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak DA REDD+ dalam upaya
meningkatkan kemampuan adaptif dan aksi adaptasi komunitas lokal. Hal ini berkaitan
dengan bagaimana perilaku komunitas lokal dalam beradaptasi membantu mewujudkan
terciptanya konservasi hutan dan pembangunan hutan berkelanjutan. Seperti yang telah
diketahui bahwa komunitas lokal desa penyangga dan kawasan hutan TNMB memiliki
hubungan yang erat terutama terkait dengan aspek ekonomi, sosial budaya serta lingkungan.
Kemampuan adaptif serta aksi adaptasi dari komunitas lokal desa penyangga dapat menjadi
acuan seberapa besar manfaat kegiatan DA REDD+ dapat membentuk perubahan perilaku
dalam pengelolaan hutan serta upaya apa yang menjadi solusi untuk mengurangi
kebergantungan kebutuhan dari hasil hutan serta mencegah kerusakan hutan.
Hutan dinilai sebagai salah satu komoditas stretegis dalam pembangunan ekonomi,
namun tidak dapat dilepaskan dari peran pembangunan sosial dimana pembangunan sosial
menjadi landasan dasar untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Ketahanan dan
ketangguhan komunitas lokal menjadi salah satu modal utamanya.
B. Tinjauan Teoritis
Kemampuan adaptif merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran
individu maupun kelompok masyarakat dalam mengantisipasi perubahan iklim yang
diwujudkan dalam implementasi perubahan perilaku aksi adaptasi, dimana hal ini diperlukan
untuk mempersiapkan diri terhadap segala kemungkinan perubahan di masa mendatang
(Spearman & McGray, 2011). Kemampuan adaptif mengacu pada potensi untuk beradaptasi,
saat dan ketika diperlukan, serta tentu otomatis bertindak adaptasi, atau hasilnya (Smit dan
Wandel, 2006 dalam Ludi, dkk 2011). Kemampuan adaptif cenderung multidimensional dan
unsur-unsur yang membentuk kapasitas adaptasi pada individu tidak sepenuhnya disetujui.
Hal ini pada dasarnya berkaitan dengan apakah masyarakat mempergunakan alat yang tepat
dan lingkungan yang kondusif diperlukan untuk mendukung kelompok komunitas
beradaptasi dalam jangka panjang. Hal penting untuk diingat bahwa kemampuan adaptif
merupakan konteks yang spesifik dan cenderung bervariasi antara negara satu dengan negara
lainnya, masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, antara kelompok-kelompok sosial dan
individu, yang terjadi dari waktu ke waktu (Smit dan Wandel, 2006 dalam Ludi dkk, 2011).
4
Gambar 1. Kerangka Local
Adaptive Capacity Sumber : ACCRA
Kemampuan adaptif kelompok komunitas akan
diidentifikasi lebih lanjut oleh peneliti dengan
menggunakan kerangka Local Adaptive Capacity (LAC)
yang dikembangkan oleh ACCRA (Africa Climate
Change Reilience Alliance). LAC difokuskan kepada
komunitas lokal dan dikembangkan untuk mengetahui
karaktersitik kemampuan adaptif kelompok komunitas
lokal setelah masa DA REDD+ di Taman Nasional Meru
Betiri. Identifikasi kemampuan adaptif komunitas lokal
menggunakan 5 (lima) komponen karaktersitik yang
berbeda tetapi sifatnya saling berkaitan satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi.
Asset base Kemampuan masyarakat dalam merespon sebuah perubahan dipengaruhi oleh aset
yang dimiliki, serta bagaimana mengakses dan mengontrol semua aset yang ada (Daze
et al., 2009; Prowse dan Scott, 2008 dalam Graham, 2012). Aset yang dimaksud antara
lain terdiri dari natural capital, physical capital, financial capital, human capital, dan
sosial capital.
Knowledge and
Information
Pengetahuan yang memadai tentang ancaman di masa mendatang terkait perubahan
iklim, metode adaptasi dan ketersediaan dukungan untuk melakukan adaptasi akan
berkontribusi terhadap kemampuan adaptif masyarakat) (Jones et al., 2010 dalam
Graham, 2012)
Innovation Inovasi berkaitan erat dengan pengetahuan dan informasi tambahan yang diperoleh
individu untuk menganalisis bagaimana mengambil peluang atau menanggapi ancaman
dari perubahan iklim. Dimana inovasi juga juga terkait erat dengan aset dasar yang
mencerminkan kondisi ekonomi seseorang dalam mengambil resiko maupun
mengembangkan investasi dalam inovasi (Ludi et al, 2011 dalam Graham, 2012)
Institutionals
and
Entitlements
Peran lembaga dan kelembagaan sangat penting untuk mengatur dan mengakui
eksistensi masyarakat dalam perannya sebagai aktor utama yang mendukung
kemampuan adaptif masyarakat untuk menjaga hutan. partisipasi masyarakat dalam
proses pembuatan keputusan pada level komunitas dinilai penting karena terkait
dengan bagaimana sebuah lembaga memberdayakan atau tidak memberdayakan
individu maupun kelompok (Jones et al, 2010 dalam Graham, 2012)
Flexible and
Forward
Thinking,
Decision
making, and
Governance
Kemampuan sebuah sistem untuk mengantisipasi perubahan, menggabungkan
informasi yang relevan serta memadukan inisiatif dalam perencanaan di masa
mendatang dan mengatur tata kelolanya merupakan aspek penting dalam menentukan
kemampuan adaptif. Hal ini terutama berkaitan dengan peran pemerintah. Pemerintah
juga diharuskan untuk adaptif dalam pengimplementasian perencanaan pengurangan
dampak perubahan iklim yang diwujudkan dalam bentuk transparansi,
memprioritaskan kerjasama, dan menggunakan informasi yang relevan dalam proses
pengambilan kebijakan. Tata kelola dan pengambilan keputusan yang demikian
cenderung lebih responsif, dan dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi untuk
mengatasi perubahan iklim dan menciptakan pembangunan hutan berkelanjutan (Jones
et al., 2010 dalam Graham, 2012)
Dalam melakukan aksi adaptasi diperlukan kemampuan adaptif yang turut menunjang
bagi pelaksanaan aksi adaptasi. Adaptasi sebagai sebuah bentuk penyesuaian dalam sistem
ekologi, sosial atau ekonomi untuk menanggapi perubahan yang tampak atau yang
diharapkan dalam rangsangan iklim serta efek dan dampak untuk mengurangi dampak negatif
dari perubahan atau mengambil keuntungan dari peluang baru (IPCC TAR, 2001). Adaptasi
5
merupakan penyesuaian perilaku dan karakteristik sistem yang akan meningkatkan
kemampuannya dalam menghadapi tekanan eksternal (Brooks, 2003 dalam Bappenas, 2012)
atau penyesuaian sistem alam atau manusia terhadap sebuah lingkungan baru atau sebuah
lingkungan yang berubah (IPCC TAR, 2001 dalam Bappenas, 2012). Keberhasilan praktik
adaptasi membutuhkan rangkaian proses yang panjang. Perilaku adaptasi individu maupun
kelompok tidak dapat tercipta secara instant dimana dibutuhkan peran kelembagaan,
kemampuan, dan keinginan untuk mewujudkan kemampuan adaptif dan upaya adaptasinya
berhasil (Adger et al, 2004 dalam Levine, Ludi, dan Jones, 2011).
C. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan di 3 (tiga) desa penyangga kawasan TNMB dalam wilayah
administratif Kabupaten Jember yang meliputi Desa Andongrejo, Desa Curahnongko dan
Desa Wonoasri. Metode penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Data yang diperoleh melalui penelitian kualitatif bersifat natural dan sifatnya dalam serta
peneliti dapat mempelajari dan turut larut dalam kondisi yang dialami oleh informan secara
alami apa adanya. Penentuan informan berdasarkan kriteria khusus yaitu memiliki
pengetahuan tentang gambaran kegiatan DA REDD+ serta informan terlibat langsung
maupun tidak langsung dalam kegiatan DA REDD+. Informan penelitian difokuskan pada
kelompok komunitas lokal yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang terdiri dari
petani rehabilitasi dan kelompok wanita, aparatur desa, polisi hutan, LSM lokal, staf Balai
Taman Nasional Meru Betiri.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa langkah (1) Observasi, meliputi
observasi sistematik dan observasi berkerangka (Hadi, 1986); (2) Wawancara (indepth
interview), metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data atau keterangan dari informan
yaitu orang yang memiliki keahlian atau pemahaman yang terbaik mengenai suatu hal yang
ingin diketahui (Silalahi, 2009). Dalam indepth interview terlebih dahulu ditentukan key
informan untuk mengidentifikasi informan yang tepat dengan menggunakan instrumen
pedoman wawancara yang berisi panduan pertanyaan. (3) Diskusi kelompok dilakukan secara
tidak formal untuk menggali informasi dari informan secara lebih mendalam. Diskusi
dilakukan dengan kelompok petani rehabilitasi.
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Kemampuan Adaptif Komunitas Lokal Desa Penyangga Pasca DA REDD+
Kegiatan DA REDD+ merupakan salah satu bentuk intervensi komunitas yang
bertujuan untuk melindungi dan melestarikan hutan, meningkatkan stok karbon hutan serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pengembangan masyarakat lokal.
6
Dengan adanya kegiatan DA REDD+ diharapkan masyarakat dapat meningkatkan
kemampuan adaptifnya. Sebagaimana UNDP (2005) dalam Lervina dan Tirpak (2006)
memaknai bahwa kemampuan adaptif merupakan tindakan awal aksi adaptasi yang dilakukan
oleh komunitas lokal, dimana dalam praktiknya dipergunakan sumberdaya secara efektif
dengan segenap pengetahuan dan informasi yang dimiliki serta teknologi yang mendukung.
Kegiatan DA REDD+ dianggap sebagai strategi pembangunan efektif untuk
mengurangi dampak perubahan iklim dimana didalamnya terdapat 3 tuntutan (triple wins)
yaitu menjaga emisi karbon hutan agar tetap rendah, membangun ketahanan komunitas lokal
terutama untuk menghadapi perubahan iklim dan mendorong pembangunan kehutanan yang
berkelanjutan dalam suatu rangkaian yang sejalan. Untuk mengetahui keefektifan tiga
tuntutan tersebut, selanjutnya dilakukan identifikasi karakteristik kemampuan adaptif
komunitas lokal melalui kerangka LAC (Local Adaptive Capacity) yang dikemukakan oleh
ACCRA (African Climate Change Resilience Alliance), sebagai berikut.
a. Asset Base (Aset Dasar)
1) Natural capital
Natural capital merupakan kekayaan sumber daya alam yang digunakan untuk
mencukupi kebutuhan sumberdaya untuk mendukung livelihood masyarakat (DFID, 1999
dalam Graham, 2012). Menurut Caravani dan Graham (2011) dalam Graham (2012),
menyebutkan bahwa, dengan mengintegrasikan penggunaan asset alam yang dimiliki oleh
masyarakat dalam desain REDD+, maka biaya peluang yang dikeluarkan oleh masyarakat
dapat diminimalisir, dan masyarakat juga akan bersedia berpartisipasi dalam REDD+.
TNMB merupakan kawasan konservasi sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : 277/Kpts-VI/1997 tanggal 23 Mei 1997, Kawasan Meru Betiri ditetapkan sebagai
Taman Nasional dimana hutan TNMB menjadi milik negara. Hak tenurial lahan hutan
menjadi penuh milik negara dan masyarakat tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun
termasuk memanfaatkan segala sumberdaya hutan yang berupa kayu maupun non kayu. Sejak
penetapan itu hak tenurial komunitas lokal atas sumberdaya hutan menjadi terbatas. Sehingga
kemudian, terjadi perambahan besar-besaran sewaktu peralihan orde baru menuju reformasi.
Untuk mengatasi hal tersebut, kemudian aset berupa lahan rehabilitasi dibagikan pada
komunitas lokal desa penyangga dengan luasan perorangan berkisar 0,25 Ha. Hal ini menjadi
bagian dari upaya pemberian hak tenurial lahan hutan dimana komunitas lokal desa
penyangga diakui kewenangannya dan terlibat langsung dalam kegiatan rehabilitasi hutan,
serta boleh memanfaatkan, mengelola dan menggunakan sumberdaya yang ada di masing-
masing lahan rehabilitasi yang dimiliki kelompok petani rehabilitasi.
Dengan adanya pengakuan hak tenurial lahan terutama pada lahan rehabilitasi, maka
kegiatan deforestasi dan degradasi dapat diminimalisir. Hal ini sejalan dengan teori yang
7
dikemukakan oleh Caravani dan Graham (2011) dalam Graham (2012), jika akses terhadap
lahan terpenuhi, maka ketahanan komunitas lokal dalam upaya mendukung terciptanya hutan
yang lestari dapat terpenuhi seiring dengan kemampuan adaptif yang dimiliki oleh komunitas
lokal. Aset berupa lahan rehabilitasi menjadi jaminan (safeguards) bagi komunitas lokal
untuk meningkatkan kesejahteraannya sehingga kemampuan adaptif komunitas lokal dalam
menghadapi pasca DA REDD+ dapat terus terlaksana dan pembangunan hutan berkelanjutan
dapat terwujud secara berkesinambungan.
2) Human capital
Human capital diidentifikasi sebagai keterampilan, pengetahuan, kemampuan bekerja
dan kesehatan yang baik yang secara bersama mendukung masyarakat untuk mengejar
strategi penghidupan yang berbeda. Human capital yang dimiliki individu maupun kelompok
untuk menyadarkan perannya dalam peningkatan konservasi karbon hutan. Karaktersitik
human capital yang dimiliki oleh kelompok masyarakat di 3 desa wilayah penelitian
memiliki tingkatan human capital yang berbeda.
Desa Curahnongko, kelompok petani rehabilitasi memiliki human capital yang bagus
dalam kaitannya denan kesadaran yang dimiliki untuk berpartisipasi dalam upaya konservasi
hutan, tetapi hal ini tidak bisa digeneralisir pada semua individu kelompok tani. Hanya
individu kelompok tani yang aktif dan dekat dengan petugas saja yang memiliki kesadaran
tinggi untuk menjaga hutannya. Sedangkan pada kelompok wanita, human capital yang
dimiliki terkait dengan kesadaran dalam upaya konservasi hutan dimiliki oleh tokoh-tokoh
wanita, namun perannya dalam mengadvokasi kelompok wanita untuk berpartisipasi menjaga
kelestarian hutan masih rendah. Sedangkan di Desa Andongrejo, human capital yang bagus
dimiliki oleh kelompok wanita yaitu ibu-ibu pengelola budidaya jamu tradisional. Hal ini
dapat dilihat dari kemampuan dan pengetahuan kelompok wanita yang dimiliki tentang
ramuan tradisional untuk berbagai macam penyakit dengan memanfaatkan apotik hidup yang
merupakan kekayaan hayati TNMB. Kelompok wanita pengelola budidaya jamu tradisonal
menjadi andalan bagi Desa Andongrejo untuk menggiatkan dan mengajak kelompok wanita
lainnya dalam upaya konservasi karbon hutan. Hal ini tidak lain dari motivasi yang dimiliki
individu untuk lebih maju dan berkembang dalam upaya meningkatkan kapasitas pribadinya
serta dukungan dari pendampingan LSM KAIL yang berpengaruh dalam menjamin
keberlangsungan kegiatan budidaya jamu tradisional yang dilakukan oleh wanita. Warisan ini
dimiliki oleh kelompok wanita yang kemudian diupayakan disebarkan melalui tetangga,
rekan, maupun keluarganya. Keinginan untuk memajukan kelompok wanita dan upaya untuk
menjaga hutan khususnya di zona rehabilitasi sangat besar. Kemampuan adaptif kelompok
wanita sangat baik dengan keikutsertaannya peduli pada upaya pelestarian hutan dan
konservasi karbon dengan tetap menjaga tanaman pokok di lahan rehabilitasi.
8
Berbeda halnya dengan kelompok wanita yang ada di Desa Wonoasri. Kelompok
wanita tidak terlalu berperan aktif dalam mewujudkan kegiatan REDD+ khususnya di
TNMB. Hal ini dikarenakan, peran pendampingan hanya terfokus pada Desa Andongrejo dan
Curahnongko, yang digagas sebagai pilot project untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat
dalam implementasi kegiatan DA REDD+ serta kurangnya motivasi dari individu masing-
masing. Potensi human capital yang dimiliki masing-masing kelompok akan berpengaruh
pada kemampuan adaptif terutama dalam upaya konservasi karbon. Semakin banyak
pengetahun yang dimiliki kelompok tani, maka semakin terampil mereka dalam melakukan
inovasi-inovasi untuk mengelola lahan dan bersikap bijak pada pengelolaan hutan TNMB.
3) Social capital
Social capital digambarkan sebagai sumber daya sosial yang dimanfaatkan untuk
mendukung tujuan peningkatan livelihood masyarakat (DFID, 1999 dalam Graham,
2012). Dalam social capital bentuk hubungan antarindividu maupun antarkelompok yang
terjalin untuk saling menguatkan satu dengan lainnya. Hal ini menjadi modal utama untuk
meningkatkan partisipasi komunitas lokal serta meningkatkan kemampuan adaptifnya baik
yang dimiliki individu maupun komunitas dalam mendukung upaya konservasi karbon hutan.
Karaketeristik social capital kelompok masyarakat TNMB cenderung berbeda dimana hal ini
akan berpengaruh pada implementasi kegiatan khususnya yang terkait dengan upaya
pelestarian hutan.
Desa Curahnongko memiliki social capital yang bagus yang terjalin antarindividu
maupun antarkelompok, dimana terlihat bahwa peran seorang ketua kelompok petani
rehabilitasi sangat mempengaruhi anggota kelompok tani lainnya. Keaktifan dan keluwesan
ketua kelompok dalam melakukan pendekatan kepada warga serta merangkul warganya
menjadi kunci untuk menghidupkan peran kelompok dalam meningkatkan kemampuan
adaptifnya. Tingginya social capital dapat dilihat dari loyalitas individu untuk berkumpul
dalam acara-acara yang diselenggarakan formal maupun informal oleh ketua kelompok tani.
Social capital di kelompok ibu-ibu pengajian di Desa Curahnongko pada dasarnya memiliki
hubungan yang kuat. Intensitas dari pertemuan mingguan dan kekompakan ibu-ibu menjadi
salah satu sasaran untuk mendekati kelompok wanita dalam upaya peningkatkan kemampuan
adaptif yang salah satunya diinisiasi oleh LSM KAIL. Upaya melibatkan kelompok
pengajian didasari pada keinginan untuk menginternalisasi upaya konservasi dalam nilai-nilai
agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat sehingga hal ini tidak hanya dipahami
sebagai bentuk kegiatan saja tapi diharapkan dapat menjadi kemasan langkah ibadah dan
menanam kebaikan. Stigma yang ditanamkan adalah dengan upaya melestarikan hutan akan
memberi manfaat tidak hanya bagi manusia sendiri, tetapi bagi makhluk ciptaan Tuhan
lainnya seperti hewan tumbuhan juga menjadi bagian dari ladang amal. Menciptakan
9
kehidupan harmonis antara alam dengan manusia adalah menjadi peran utama manusia
sebagai khalifah di bumi.
Kelompok wanita pengelola budidaya jamu tradisional di Desa Andongrejo memiliki
gambaran social capital yang bagus. Hal ini terlihat dari keaktifan kelompok untuk
mengembangkan ramuan jamu yang berkhasiat mengobati berbagai jenis penyakit serta
keaktifannya dalam perkumpulan pengajian mingguan. Kelompok ini sudah terbentuk sejak
Tahun 1993 oleh LSM LATIN (Bogor). Kondisi social capital kelompok wanita di Desa
Andongrejo menjadi salah satu potensi dalam upaya melibatkan partisipasi masyarakat
khususnya kelompok wanita untuk turut serta meningkatkan konservasi karbon. Kesadaran
dan peran pentingnya kelompok wanita dalam menjaga hutan diharapkan dapat menjadi
kunci untuk bersama meningkatkan kepedulian terhadap hutan demi kelestarian hutan dan
terjaminnya kesejahteraan komunitas lokal.
Lain halnya dengan kondisi di Desa Wonoasri, dimana merupakan desa yang tidak
mendapat pendampingan langsung dari LSM. Namun peran social capital yang dimiliki
antarindividu maupun antarkelompok petani dalam upaya konservasi karbon hutan cukup
besar. Baik antarindividu maupun antarkelompok terjadi hubungan timbal balik untuk saling
mengingatkan. Hal ini juga didukung oleh peran aparatur desa yang juga turut aktif untuk
melakukan pendekatan kepada kelompok komunitas terkait dengan upaya-upaya apa yang
dapat mendukung terciptanya hutan lestari. Peran aparatur desa mendapat dukungan positif
dari kelompok komunitas lokal, sehingga hubungan sinergi keduanya dapat meningkatkan
kepedulian bersama dalam upaya konservasi karbon hutan.
4) Financial capital
Financial capital dipandang sebagai sumber daya keuangan yang digunakan
masyarakat untuk mengadopsi strategi mata pencaharian yang berbeda (DFID,1999
dalam Graham, 2012). Berkaitan dengan kondisi financial capital yang dimiliki oleh
komunitas lokal desa penyangga terkait dengan kemampuan yang dimiliki komunitas
untuk mengalihkan mata pencaharian alternatif untuk mengurangi interaksi dan
ketergantungan terhadap hasil hutan di kawasan TNMB. Dengan demikian,
kemampuan adaptif komunitas lokal dalam upaya konservasi karbon dapat terwujud
melalui strategi pengembangan mata pencaharian alternati f, dimana komunitas lokal
desa penyangga tidak selalu mengandalkan kehidupannya pada hasil hutan berupa
kayu saja melainkan dengan melakukan budidaya dari hasil hutan berupa non kayu
untuk diolah agar memberikan nilai tambah.
b. Knowledge and Information (Pengetahuan dan Informasi)
Menurut Frankhauser dan Tol (1997) dalam Graham (2012) mengemukakan bahwa
langkah bagaimana sebuah informasi dihasilkan, dikumpulkan, dianalisis dam disebarluaskan
10
akan menjadi penting dalam menentukan kemampuan adaptif kelompok masyarakat. Hal ini
jelas berkaitan erat dengan keberadaan lembaga-lembaga, dan masyarakat yang akan
membutuhkan sistem untuk mengoptimalkan generasi pengetahuan informal dan berbagi
serta terbaik memanfaatkan jenis pengetahuan yang lebih formal.
Pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat serta informasi yang didapat melalui
kegiatan DA REDD+, akan berpengaruh pada kemampuan adaptif komunitas lokal. Semakin
banyak pengetahun dan informasi yang diperoleh, serta pemahaman dari rangkaian kegiatan
dan tujuan DA REDD+, komunitas lokal dapat membangun kesadarannya serta memiliki
banyak pilihan untuk menentukan aksi adaptasi dalam upaya konservasi karbon hutan demi
menjamin kesejahteraan hidup masyarakat masa sekarang maupun di masa yang akan datang
tanpa merusak fungsi hutan.
Dalam proses transferability, akan diperoleh informasi dan pengetahuan yang dimiliki
komunitas lokal baik pada kelompok petani rehabilitasi maupun kelompok wanita.
Rekonstruksi pemahaman informan pada kedua kelompok terkait dengan REDD+ merupakan
salah satu upaya untuk mengidentifikasi kemampuan adaptif komunitas lokal pasca kegiatan
DA REDD+. Karakteristik kemampuan adaptif komunitas lokal cenderung berbeda
antarkelompok dan antardesa di wilayah penelitian. Kemampuan adaptif yang dimiliki
komunitas lokal untuk mengatasi perubahan ketika dan di saat dibutuhkan cenderung berbeda
antara tempat yang satu dengan lainnya maupun antarkomunitas satu dengan lainnya, serta
antarwaktu yang berbeda pula (Smit dan Wandel, 2006 dalam Ludi dkk, 2011).
Dalam komunitas lokal desa penyangga, istilah REDD+ bukan merupakan istilah yang
mudah dimengerti bagi komunitas lokal. REDD+ lebih dipahami sebagai salah satu upaya
pelestarian hutan khususnya di lahan rehabilitasi yang dilakukan dengan cara menjaga
tanaman pokok sebagai penghasil karbon. Kelompok komunitas lokal di Desa Andongrejo
dan Curahnongko lebih memahami mengenai konsep REDD+ yang diwujudkan dalam
sebagian perilaku upaya konservasi karbon hutan. Kesadaran dan kepedulian untuk
pelestarian hutan di Desa Curahnongko dan Andongrejo tidak dapat digeneralisir bahwa
masyarakat menyadari dan bertindak menghijaukan hutan. Masih terdapat kelompok
masyarakat yang tidak memiliki kesadaran penuh atas peran dan fungsi hutan. Tetapi
cenderung lebih mementingkan kegiatan ekonomi dan sibuk mensejahterakan pribadinya
dengan tindakan yang melanggar hukum.
Lain halnya dengan kelompok komunitas Desa Wonoasri, khususnya kelompok petani
rehabilitasi yang tidak mengikuti kegiatan DA REDD+ terlihat kurang memahami dan
familiar dengan istilah REDD+. REDD+ hanya dipahami oleh sebagian kelompok petani
rehabilitasi yang mengikuti kegiatan REDD+ dan petugas resort Wonoasri. Peran kelompok
petani sendiri tidak begitu besar untuk menyatakan bahwa mereka benar-benar melakukan
11
transferability tersebut kepada anggota kelompok tani lainnya. Namun uniknya adalah lahan
rehabilitasi yang dimiliki oleh petani di Desa Wonoasri memiliki tingkat kerapatan tanaman
yang lebih baik jika dibandingkan dengan dua desa lainnya. Hal ini dikarenakan kesadaran
komunitas lokal sendiri untuk ikut serta menjaga hutan di lahan rehabilitasi yang dimiliki
petani. Walaupun pengetahuan tidak diperoleh secara merata pada elemen kelompok
masyarakat, tingkat kesadaran dan kepeduliannya untuk menjaga hutan masih relatif bagus
jika dibandingkan dengan dua desa lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses
transferability terkait pengetahuan REDD+ tidak dapat berjalan optimal.
Tetapi nilai pentingnya adalah kesadaran individu maupun kelompok dalam upaya
konservasi karbon hutan cenderung baik. Hal ini berkorelasi dengan hubungan yang
terbentuk antara komunitas lokal dengan hutan tidak memiliki keterkaitan langsung, artinya
dalam hal ekonomi, komunitas lokal Desa Wonoasri tidak bergantung sepenuhnya pada
hutan, karena sebagian besar masyarakat lebih mengandalkan bekerja sebagai buruh
perkebunan yang banyak mengelilingi kawasan TNMB. Kegiatannya di lahan rehabilitasi
hanya sebagai sampingan saja. Tetapi kesadaran untuk tetap menjaga hutannya disadari
cukup baik.
Berdasarkan pengamatan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa transferability akan
berpengaruh pada tingkat kesadaran dari pengetahuan yang diperoleh dimana akan
mempengaruhi kemampuan adaptif komunitas lokal sehingga dapat mempraktikkan upaya-
upaya konservasi karbon hutan.
c. Innovation (Inovasi)
Seperti pada teori Ludi (2011) dalam Graham (2012), menyebutkan bahwa inovasi
berkaitan erat dengan pengetahuan dan informasi tambahan yang diperoleh individu untuk
menganalisis bagaimana mengambil peluang atau menanggapi ancaman dari perubahan
iklim. Dimana inovasi juga terkait erat dengan aset dasar yang mencerminkan kondisi
ekonomi seseorang dalam mengambil resiko maupun mengembangkan investasi dalam
inovasi. Inovasi antarindividu maupun antarkelompok cenderung berbeda sesuai dengan
pengetahuan dan informasi yang diperoleh serta kesadaran yang dimiliki. Dalam hal ini
menggambarkan bahwa semakin banyak individu maupun kelompok terlibat dalam rangakain
kegiatan DA REDD+ semakin banyak informasi dan pengetahuan yang dimiliki sehingga
inovasinya akan semakin baik. Banyak hal baru yang akan dilakukan (inovasi) dalam upaya
mempraktikkan dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki sebagai bentuk wujud
kemampuan adaptif (Gambar 2).
12
Gambar 2. Hubungan keterkaitan komponen dalam membentuk kemampuan adaptif
Kemampuan sebuah sistem dalam mendukung praktik baru dan meningkatkan inovasi
menjadi kunci utama dalam menentukan karakteristik perilaku adaptif. Sistem yang dimaksud
adalah seluruh pihak yang terlibat dan bertanggungjawab dalam menciptakan keharmonisan
di alam, yaitu manusia (yang terdiri dari komunitas lokal maupun peran institusi).
Berdasarkan hasil temuan lapangan inovasi akan dikelompokkan menjadi 3 yaitu Pertama,
inovasi budidaya tanaman yang dilakukan oleh kelompok petani rehabilitasi dengan
menanam tanaman yang memiliki kandungan dan serapan karbon tinggi serta
menguntungkan dari segi ekonomis, dan tahan terhadap naungan yang teduh sehingga
pertumbuhannya tidak terganggu. Untuk mewujudkan inovasi tersebut, dilakukan dengan
metode MPTS (Multi Purpose Trees Species). Hal ini untuk mengakomodir kepentingan
masyarakat karena pada dasarnya masyarakat memiliki ketergantungan tinggi terhadap hasil
hutan.
Kedua, Inovasi untuk meningkatkan pendapatan melalui program pemberdayaan
masyarakat. Dalam hal ini beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu dengan mengembangkan
tanaman empon-empon untuk budidaya pengelolaan jamu tradisional dengan sistem
agroforestry serta pembudidayaan jamur tiram. Hal ini menjadi upaya untuk memberikan
kontribusi alternatif peningkatan pendapatan ketika rapatan tegakan hutan semakin tinggi,
sehingga tercipta kreasi baru dari petani untuk menanam tanaman yang lain dan bernilai
ekonomis. Salah satu penerapannya dilakukan di Desa Andongrejo yang menyasar pada
kelompok wanita pengelola budidaya jamu tradisional.
Ketiga, Inovasi pengelolaan lahan rehabilitasi. Inovasi untuk meningkatkan motivasi
konservasi hutan diwujudkan melalui program PINTAR. Program PINTAR merupakan
bentuk apresiasi kepada petani rehabilitasi yang berhasil menjaga tanamannya di lahan
rehabilitasi sesuai dengan skema sistem pengkelasan lahan berdasarkan jumlah rapatan
tanaman pokok/tegakan yang ada. Program ini hanya diterapkan di Desa Curahnongko dan
Adaptive capacity
Asset base
Information &
Knowledge Innovation
Intervention Intervention
Opportunity
Threathness
13
Andongrejo dengan inisiasi LSM KAIL. Tujuan program PINTAR adalah untuk
meningkatkan dan membangun partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi karbon hutan.
Dimana penerapannya diberlakukan pada petani yang memiliki lahan rehabilitasi dengan nilai
kelas lahan pada peringkat 5 dan 6 yang menggambarkan bahwa kerapatan tanaman di
rehabilitasi sudah mencapai antara 100 hingga 150 pohon. Petani tersebut kemudian akan
diberikan keringanan harga beli sembilan bahan pokok sebesar Rp 3.000,- di toko yang telah
disediakan, dengan maksimal jumlah pemotongan satu tahun sebesar Rp 150.000,- per orang.
Upaya pelibatan partisipasi masyarakat untuk menjaga kawasan hutan TNMB khususnya
yang berbatasan langsung dengan zona rimba pada lahan rehabilitasi juga diinisiasi oleh LSM
KAIL melalui pemetaan partisipatif. Pemetaan partisipatif ditujukan untuk meningkatkan
komitmen dan kesadaran komunitas lokal maupun kelompok petani rehabilitasi untuk
bertanggungjawab dalam konservasi karbon hutan dengan tidak melakukan perambahan.
Namun, kegiatan ini hanya mampu diimplementasikan pada kelompok petani rehabilitasi di
Desa Curahnongko karena keterbatasan pembiayaan program.
Menurut Smith et al (2003) dalam Graham (2011), kemampuan sebuah sistem dalam
mendukung praktik baru dan meningkatkan inovasi menjadi kunci utama dalam menentukan
karakteristik kapasitas adaptif. Hal ini tentunya dibutuhkan perubahan kondisi sosial dan
lingkungan serta praktik-praktik. Beberapa inovasi tersebut telah diwujukan oleh LSM KAIL
khususnya di kelompok komunitas Desa Andongrejo dan Curahnongko. Berpedoman pada
Teori Smith, melalui pengamatan yang dilakukan di Desa Curahnongko dan Andongrejo
dapat disimpulkan bahwa dukungan kelembagaan LSM cukup efektif untuk mengubah
perilaku adaptif kelompok masyarakat dalam upaya konservasi hutan. Intervensi LSM KAIL
dalam bidang pengembangan masyarakat lokal dapat meningkatkan inovasi dan motivasi
komunitas untuk meningkatan kondisi livelihoodnya. Hal yang terlihat adalah berkurangnya
ketergantungan kelompok komunitas lokal terhadap hasil hutan yang berupa kayu. Ditandai
dengan tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal melalui pengelolaan hasil hutan non kayu sebagai
produk olahan inovatif.
Upaya LSM KAIL dalam melakukan inovasi yang menyentuh level mikro dianggap
sebagai cara efektif yang mampu menjadi solusi untuk menciptakan peluang dan respon
terhadap konservasi karbon hutan khususnya di Kawasan TNMB.
d. Institutions and Entitlements (Dukungan Kelembagaan dan Persamaan Hak)
Dukungan kelembagaan memiliki pengaruh penting dalam meningkatkan
kemamampuan adaptif sebagaimana dijelaskan dalam teori yang dikemukakan oleh Jones et
al (2010) dalam Graham (2012). Lembaga merupakan kontrol dari sistem regulasi dan
struktur organisasi yang ada, dimana lembaga tersebut dapat bersifat formal (lembaga
pemerintahan) maupun non formal (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) (Ostrom, 2005
14
dalam Graham, 2012). Adaptabilitas dan fleksibilitas suatu lembaga akan mempengaruhi
peran komunitas dalam menentukan kapasitas adaptifnya. Kondisi ini tidak terlepas dari
eksistensi peran lembaga dalam mengatur dan menciptakan partisipasi kelompok masyarakat
dalam upaya perwujudan konservasi karbon di TNMB. Dukungan kelembagaan dalam hal ini
lebih menitikberatkan pada penguatan karena lembaga di tingkat lokal sudah terbentuk sejak
sebelum diselenggarakannya DA REDD+, sehingga dalam masa periode kegiatan DA
REDD+ eksistensi lembaga ini lebih diperkuat perannya khususnya di tingkat lokal dengan
meningkatkan partisipasi masyarakat.
Dukungan kelembagaan yang berasal dari kegiatan pendampingan LSM KAIL lebih
dipusatkan pada dua desa yaitu Desa Curahnongko dan Andongrejo. Melalui dukungan
kelembagaan pada kelompok petani rehabilitasi dan kelompok wanita, tingkat ketahanan
dalam membentuk kapasitas adaptif untuk upaya konservasi karbon dirasa memiliki potensi
besar dengan melibatkan partisipasi komunitas lokal. Dukungan pada kelompok petani
rehabilitasi dilakukan melalui pembentukan kelembagaan semi formal antar anggota
kelompok petani rehabilitasi serta beberapa usaha budidaya untuk mengurangi
kebergantungan kelompok petani rehabilitasi pada hasil hutan serta dapat meningkatkan
pendapatannya. Sedangkan pada kelompok wanita, upaya yang dilakukan yaitu melalui
budidaya pengelolaan jamu tradisional, dimana penguatan kelembagan menjadi salah satu
bekal untuk mewujudkan eksistensi kelompok wanita. Perannya begitu penting dalam
melakukan persuasif terhadap anggota kelompok wanita lainnya untuk kegiatan rehabilitasi
hutan. Hal ini dapat terlihat di Desa Andongrejo yang dilihat dari keaktifan dan eksistensi
kelompok wanita pengelola jamu tradisional. Sedangkan di Desa Curahnongko, penguatan
kelompok wanita pada kelembagaan semi formal yaitu perkumpulan ibu-ibu pengajian
menjadi andalan bagi upaya penyadaran kelompok wanita yang ditanamkan melalui elemen
agama dan budaya.
Peran pemerintah juga penting dalam upaya meningkatkan kemampuan adaptif
komunitas lokal. Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya peningkatan kapasitas
kelembagaan misalnya SPKP (Sentra Penyuluhan Kehutanan Perdesaan), MMP (Masyarakat
Mitra Polhut), serta peran resort/polisi hutan. Pemerintah telah berupaya untuk melibatkan
masyarakat dalam upaya pengawasan dan perlindungan hutan dengan adanya MMP, sehingga
diharapkan partisipasi aktif kelompok komunitas dalam MMP menjadi bagian dari wujud
peningkatan kemampuan adaptif dari terselenggaranya kegiatan DA REDD+.
e. Flexible and Forward Thinking, Decision making, and Governance (Fleksibilitas dan
Orientasi Ke Depan, Pengambilan Keputusan, serta Tata Kelola Pemerintahan)
Menurut Jones et al (2010) dalam Graham (2012), kemampuan sebuah sistem untuk
mengantisipasi perubahan, menggabungkan informasi yang relevan serta memadukan inisiatif
15
dalam perencanaan di masa mendatang dan mengatur tata kelolanya merupakan aspek
penting dalam menentukan kemampuan adaptif. Hal ini terutama berkaitan dengan peran
pemerintah dan LSM lokal terkait. Dalam sebuah sistem yang bekerja diperlukan keterlibatan
secara bersama untuk menciptakan sebuah komponen utuh yang saling bekerjasama.
Pihak manajemen Balai TNMB telah berupaya melibatkan partisipasi komunitas dalam
upaya menjaga hutan melalui pembentukan Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Setiap desa
penyangga dibentuk MMP yang anggotanya dipilih dari kelompok petani rehabilitasi yang
memiliki peran penting dalam struktur kelompok dan aktif dalam setiap kegiatan. Tata
kepemerintahan dengan struktur, mekanisme dan institusi-institusinya adalah kunci penentu
bagi kemampuan adaptif (Adger et al 2004;Brooks et al 2005 dalam Locatelli, dkk, 2009)
karena ia menentukan kerangka dimana adaptasi terjadi atau dimana adaptasi dibutuhkan
(Locatelli, dkk 2009).
Selain upaya perlindungan terhadap hak tenurial atas masyarakat desa penyangga,
diperlukan sistem hukum yang tegas terhadap sejumlah aksi illegal logging yang dinilai
cukup merugikan. Keberanian institusi pemerintah untuk menerapkan hukuman yang tegas
bagi pelaku illegal logging sangat menentukan bagi keberlangsungan kelestarian hutan
TNMB. Pada dasarnya kegiatan illegal logging tidak hanya merugikan bagi pihak pemerintah
saja, melainkan juga bagi komunitas desa penyangga sendiri dimana dampaknya akan
dirasakan ketika hutan semakin gundul berdampak pada bencana lokal yang tidak dapat
diprediksi datangnya.
2. Aksi Adaptasi Komunitas Lokal Desa Penyangga Pasca DA REDD+
Adaptasi merupakan penyesuaian perilaku dan karakteristik sistem yang akan
meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi tekanan eksternal (Brooks, 2003 dalam
Bappenas, 2012) atau penyesuaian sistem alam atau manusia terhadap sebuah lingkungan
baru atau sebuah lingkungan yang berubah (IPCC TAR, 2001 dalam Bappenas, 2012). Proses
pembangunan aksi adaptasi diawali dengan pembangunan kemampuan adaptif melalui
intervensi sosial dimana tujuan intervensi adalah mencari cara bagaimana meningkatkan
kualitas dan ketersediaan kebutuhan sumberdaya untuk diadaptasi, atau bagaimana mengolah
kemampuan untuk menggunakan sumberdaya secara efektif.
Keterbatasan sumberdaya lahan menjadikan hutan sebagai tumpuan hidup bagi
komunitas lokal desa penyangga. Namun, mereka menyadari perannya sebaagi manusia,
tidak boleh melakukan ekploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya hutan. Komunitas
lokal desa penyangga merupakan ujung tombak sekaligus aktor kunci bagi upaya konservasi
hutan maupun semua keberlangsungan program kegiatan DA REDD+ di TNMB. Adaptasi
terhadap hutan akan sangat penting untuk mendorong upaya mengatur dan menjaga stok
16
karbon dalam jangka panjang, meskipun di banyak wilayah struktur dan fungsi hutan telah
berubah sejak lama (Noss, 2001 dalam Graham, 2011). Perubahan dapat dimimalisir dengan
melakukan adaptasi sebagai upaya mitigasi kerusakan hutan.
Dengan mengetahui pandangan masyarakat terhadap hutan TNMB dan pemahaman
yang tercipta atas konstruksi kegiatan DA REDD+ dapat menjadi kontiribusi penting bagi
upaya penerapan aksi adaptasi yang dilakukan setelah kegiatan DA REDD+ berlangsung.
Berdasarkan hasil analisis keterangan dari kelompok komunitas lokal desa penyangga,
keterkaitan hubungan yang terjalin antara komunitas lokal dengan hutan tergambarkan ke
dalam 5 konsep yaitu (1) Masyarakat bertanggungjawab atas upaya pelestarian hutan; (2)
Hutan sebagai sumber mata pencaharian; (3) Hutan sebagai alternatif mata pencaharian; (4)
Keterbatasan sumberdaya lahan di sekitar kawasan TNMB; dan (5) Hutan memiliki manfaat
bagi ekosistem lingkungan. Secara umum dapat dismpulkan bahwa keterkaitan hubungan
antara komunitas lokal desa penyangga dengan hutan TNMB bergantung pada kedekatan
lokasi geografis kawasan yang pada akhirnya akan juga berpengaruh pada tingkat adaptasi
dan tuntutan dalam menjalankan keberlangsungan kehidupannya.
Dalam mewujudkan ketercapaian tujuan dari adanya kegiatan DA REDD+ di kawasan
TNMB perlu dilakukan kajian terhadap aksi adaptasi yang telah dilakukan oleh kelompok
komunitas beserta stakeholder yang terkait langsung dengan eksistensi kawasan TNMB. Aksi
adaptasi perlu didukung oleh semua komponen komunitas lokal , baik individu, kelompok-
kelompok formal/informal, maupun pemerintah dimana dalam keberhasilannya diperlukan
waktu yang tidak singkat karena di dalamnya membutuhkan proses penyadaran dan
pemahaman atas sesuatu hal yang baru dan memerlukan pembiasaan. Peran aktif
kelembagaan baik pemerintah maupun non pemerintah, kemampuan serta keinginan seluruh
komponen untuk bekerjasama membangun sebuah aksi adaptasi dalam upaya konservasi
karbon hutan. Berikut berbagai aksi adaptasi yang dilakukan oleh kelompok komunitas lokal
desa penyangga TNMB.
a. Kelompok petani rehabilitasi
Kemampuan adaptif komunitas lokal untuk melakukan sejumlah inovasi terkait dengan
upaya pengurangan kebergantungan terhadap hutan yang dilakukan melalui pengelolaan
lahan rehabilitasi dimana dalam implementasinya melalui penanaman sejumlah tanaman
pokok yang memilki kandungan serapan karbon tinggi juga memiliki nilai ekonomis serta
tidak merusak ekosistem hutan. Aksi adaptasi kelompok petani rehabilitasi tidak terlepas dari
peran pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM KAIL. Intervensi pemberdayaan masyarakat
dalam rangkaian kegiatan DA REDD+ dilakukan di 2 (dua) desa yaitu Desa Andongrejo dan
Desa Curahnongko. Kedua desa tersebut menjadi pilot project penerapan keberhasilan upaya
pengembangan masyarakat dalam pengelolaan hutan TNMB khususnya di lahan rehabilitasi.
17
Kelompok petani rehabilitasi turut serta dalam menjaga tanaman pokok/tegakan melalui
kesepakatan bersama untuk tidak melakukan penebangan serta melakukan penyulaman jika
terdapat tanamanpokok/tegakan yang roboh dan mati. Penyulaman tanaman di lahan
rehabilitasi menggunakan bibit swadaya mandiri maupun dengan bibit pemberian pihak Balai
TNMB.
Aksi adaptasi yang dilakukan kelompok komunitas lokal khususnya petani rehabilitasi
di Desa Andongrejo dan Curahnongko terbentuk berdasarkan binaan LSM. Hal ini sesuai
dengan teori yang dikemukakan oleh Levine, Ludi, dan Jones (2011), bahwa intervensi
dinilai membantu masyarakat maupun komunitas untuk beradaptasi kepada pola baru yang
terbentuk dari lingkungan alam, sosial ekonomi dan politik serta hubungan diantara ketiga
komponen tersebut.
Lain halnya dengan aksi adaptasi upaya konservasi karbon hutan di Desa Wonoasri
yang dilakukan tanpa pendampingan LSM. Kesadaran komunitas lokal menjadi bagian
penting dalam upaya rehabilitasi hutan. Tanpa pendampingan LSM, kelompok petani
rehabilitasi secara mandiri mampu melakukan aksi adaptasinya yang terwujud ke dalam
upaya menjaga tanaman pokok di masing-masing lahan rehabilitasi. Teori yang dikemukakan
oleh Levine, Ludi, dan Jones (2011), mengenai peran intervensi dalam keberhasilan aksi
adptasi tidak sepenuhnya dibenarkan dalam fenomena yang terjadi di Desa Wonoasri.
Sebelum adanya kegiatan DA REDD+, komunitas lokal Desa Wonoasri sudah memiliki
kesadaran untuk menjaga hutan dan lahan rehabilitasinya. Hal ini tidak lain karena, kesadaran
yang dimiliki serta rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap komitmen yang telah disepakati
bersama antara pemerintah dengan kelompok petani rehabilitasi.
b. Kelompok wanita
Kelompok wanita memiliki peran dan kedudukan penting dalam mendukung
terciptanya aksi adaptasi, dimana keterlibatannya menjadi sangat diperhitungkan bila
dikaitkan dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Di Desa Andongrejo, pelibatan kelompok
wanita lebih menyasar pada kegiatan yang berdampak langsung pada ekonomi, dimana
perannya cukup strategis dalam mendukung keberhasilan program rehabilitasi hutan TNMB.
Hubungan keterkaitan antara kondisi tanaman pokok/tegakan akan berpengaruh pada
tanaman yang hidup dibawah naungan. Jika hutan terganggu, maka kegiatan ekonominya
akan terganggung pula, sehingga secara tidak langsung kesadaran untuk mejaga hutan akan
terbentuk melalui aksi adaptasi dan upaya persuasif pada kelompok wanita lainnya untuk
turut menjaga tanaman pokok/tegakan yang ada di lahan rehabilitasi.
Sedangkan di Desa Curahnongko, internalisasi agama dan wujud pengetahuan menjadi
bekal utama dalam membentuk stigma upaya konservasi karbon hutan di kalangan kelompok
wanita. Agama menjadi dasar kuat bagi sebagian besar komunitas lokal di desa penyangga,
18
dimana karakteristik masyarakat Jember secara umum dipandang sebagai karakter
masyarakat yang agamis. Peran kelompok wanita di Desa Wonoasri berbeda dengan
gambaran di Desa Andongrejo dan Curahnongko. Peran kelompok wanita tidak nampak pada
Desa Wonoasri, dimana kelompok wanita cenderung pasif. Kelompok wanita tidak memiliki
pengaruh penting dalam sistem sosial yang berkembang di masyarakat. Selain itu, tidak
adanya peran pendampingan LSM lokal dalam upaya pemberdayaan wanita membuat
kepedulian kelompok wanita dalam upaya konservasi hutan tidak cukup menonjol.
c. Aparatur Desa
Dukungan aparatur desa akan mempengaruhi kemampuan (abilitiy) kelompok
masyarakat untuk melakukan aksi adaptasi nyata terhadap konservasi karbon hutan TNMB.
Sejumlah upaya telah dilakukan pihak pemerintah desa yang bekerjasama dengan Balai
TNMB, polisi hutan dan LSM lokal untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran
komunitas lokal pada upaya perlindungan hutan.
d. LSM KAIL
Dalam mendukung aksi adaptasi tidak terlepas dari peran dukungan pemerintah
maupun LSM lokal yang membantu meningkatkan kemampuan adaptif komunitas lokal
untuk melakukan aksi adaptasinya terutama untuk mendukung konservasi karbon hutan.
Sebelum adanya kegiatan DA REDD+ telah terbentuk kelembagaan sederhana yang terdiri
dari kelompok petani rehabilitasi dengan fokus kegiatannya yaitu pada upaya pelestarian
hutan kembali khususnya di lahan rehabilitasi. Namun, sejak berlangsungnya kegiatan DA
REDD+, dilakukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dengan melibatkan peran aktif
petani rehabilitasi sebagai pelaku utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan
keberadaan hutan TNMB dan kegiatan konservasi. Dukungan kelembagaan memiliki peran
penting dalam upaya aksi adaptasi yang dilakukan oleh komunitas lokal.
Levine, Ludi, dan Jones (2011) menyebutkan bahwa kondisi lingkungan yang
mendukung diperlukan untuk memastikan bahwa individu maupun kelompok komunitas
mampu membuat perubahan yang diperlukan untuk menanggapi perubahan iklim serta
perubahan lain yang mungkin ditimbulkan. Dengan diterapkannya pola pendampingan
pemberdayaan masyarakat di Desa Andongrejo dan Curahnongko, kelompok petani
rehabilitasi maupun kelompok wanita memliki ketahanan untuk menanggapi kebijakan dari
dari DA REDD+ dimana perolehan hak tenurial sudah diakui oleh pemerintah. Komunitas
lokal desa penyangga dilibatkan secara langsung dalam upaya konservasi karbon hutan
melalui pengakuan hak pengelolaan atas lahan rehabilitasi.
e. Polisi hutan/resort
Aksi adaptasi diwujudkan melalui kegiatan pengawasan dan perlindungan kawasan
hutan sesuai dengan tupoksinya. Resort bertanggungjawab dalam menjaga keamanan
19
kawasan hutan TNMB dengan upaya mendekatkan diri dengan masyarakat sebagai bagian
dari bentuk pendekatan partisipastif. Kemampuan resort untuk menjaga hutan tidak bisa
terlepas dari peran keterlibatan komunitas lokal. Kedua komponen ini pada dasarnya
memiliki sifat saling mendukung satu dengan lainnya. Sebagaimana Smith (2000)
mengemukakan bahwa adaptasi perlu didukung oleh semua komponen masyarakat, baik
individu, kelompok-kelompok, dan pemerintah. Kebersamaan untuk saling mendukung antar
komponen stakeholder dalam mewujudkan aksi adaptasi memiliki pengaruh yang besar.
f. Balai TNMB
Pemerintah khususnya Manajemen Balai TNMB, memiliki kekuatan penuh dalam
pengawasan dan pelaksanaan fungsi untuk meningkatkan aksi adaptasi komunitas lokal
dalam kegiatan konservasi karbon hutan serta meningkatkan stok karbon hutan sebagai
bagian dari salah satu tujuan dari terselenggaranya DA REDD+. Salah satunya dengan
melakukan pengaturan kelembagaan. Membangun kelembagaan di tingkat lokal komunitas
dapat menciptakan hubungan kedekatan antara pemerintah dengan komunitas lokal.
Keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan hutan yang berkelanjutan tidak
dapat terlepas dari aksi adaptasi seluruh komponen yang ada baik yang berkaitan langsung
dengan hutan maupun tidak langsung. Atribut dari kapasitas kepemerintahan dan individu,
organisasi atau komunitas untuk beradaptasi menentukan keberhasilan adaptasi terhadap
perubahan iklim (Pelling dan High 2005 dalam Locatelli 2009).
E. Kesimpulan
1. Kemampuan masyarakat dalam merespon sebuah perubahan adaptif dipengaruhi oleh aset
yang dimiliki, serta bagaimana mengakses dan mengontrol semua aset yang ada.
2. Aset dasar yang dimiliki kelompok komunitas lokal terdiri dari natural capital, human
capital, social capital dan financial capital.
3. Dukungan kelembagaan memiliki pengaruh penting dalam meningkatkan kemampuan
adaptif dimana peran lembaga sebagaikontrol dari sistem regulasi dan struktur organisasi
memberikan nilai positif bagi upaya pengembangan pemberdayaan masyarakat.
4. Langkah bagaimana sebuah informasi dihasilkan, dikumpulkan, dianalisis dam
disebarluaskan akan menjadi penting dalam menentukan kemampuan adaptaif kelompok
masyarakat.
5. Inovasi antar individu maupun kelompok cenderung berbeda sesuai dengan pengetahuan
dan informasi yang diperoleh. Dalam hal ini menggambarkan bahwa semakin banyak
seseorang maupun kelompok terlibat dalam rangakain kegiatan DA REDD+, maka
inovasinya akan lebih baik.
20
6. Kemampuan sebuah sistem untuk mengantisipasi perubahan, menggabungkan informasi
yang relevan serta memadukan inisiatif dalam perencanaan di masa mendatang dan
mengatur tata kelolanya merupakan aspek penting dalam menentukan kemampuan adaptif
komunitas lokal.
7. Kegiatan DA REDD+ menjadi salah satu bentuk intervensi sosial dalam proses
membangun aksi adaptasi melalui upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dengan
meningkatkan peran aktif masyarakat.
F. Saran
Pelaksanaan kegiatan DA REDD+ di TNMB khususnya terkait dengan pemberdayaan
masyarakat pada komunitas lokal di 3 desa penyangga menunjukkan bahwa kemempuan
adaptifnya cenderung beragam. Intervensi melalui pendampingan LSM pada Desa
Andongrejo dan Curahnongko cenderung lebih efektif dalam menunjang keberhasilan
program DA REDD+ sebagai upaya konservasi karbon hutan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pendampingan yang selama ini hanya terfokus pada dua
desa penyangga dari 12 total desa penyangga yang ada, terkesan timpang. Oleh karena itu,
dalam praktik selanjutnya diperlukan peran pendampingan LSM dalam upaya pemberdayaan
masyarakat. Hal ini secara tidak langsung akan berkorelasi pada karakter kemampuan adaptif
yang dimliki oleh komunitas lokal setempat dalam menanggapi DA REDD+. Gambaran ini
menjadi masukan bagi pihak Litbang Kehutanan sebagai Koordinator Project DA REDD+ di
Kawasan TNMB.
Daftar Pustaka
Arifanti, V. B., Bainnaura, A., & Ginoga, K. L. (2010). Landcover Change Analysis Using Remote Sensing and
GIS : Initial Phase of Measuring Carbon Sequestration for REDD+ in Meru Betiri National Park,
Indonesia. Bogor: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan.
Balai Taman Nasional Meru Betiri. (2012). Buku Informasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Taman
Nasional Meru Betiri. Jember: Balai Taman Nasional Meru Betiri.
Bappenas. (2012). Buku 1 Strategi Pengarusutamaan Adaptasi ke Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
: Kerangka Integrasi . Jakarta: Kementerian Bappenas.
Graham, Kristy. (2012). REDD+ and Adaptation : Will REDD+ Contribute to Adaptive Capacity at The Local
Level. Overseas Development Institute.
Hadi, Sutrisno. (1986). Metode Observasi. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM.
Heriyanto, N M; Garsetiasih, R; Subiandono, Endro. (2006). Pemanfaatan Sumberdaya Hutan oleh Masyarakat
Lokal di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam
Volume III Nomor 2 , 297-308.
IPCC. (2001). Climate Change 2001 : Impacts, Adaptation and Vulnerability . Geneva: World Meteorological
Organisation.
Levina, E., & Tirpak, D. (2006). Adaptation to Climate Change : Key Terms. France: OECD.
Levine, Simon; Ludi, Eva; Lindsay Jones. 2011. Rethinking Support for Adaptive Capacity to Climate Change :
Role of Development Interventions. Ethiopia : ODI.
21
Locatelli, B., Kanninen, M., Brochaus, M., Colfer, C. P., Murdiyarso, D., & Santoso, H. (2009). Menghadapi
Masa Depan yang Tak Pasti : Bagaimana Hutan dan Manusia Beradaptasi terhadap Perubahan Iklim .
Bogor: CIFOR.
Ludi, E., Getnet, M., Wilson, K., Tesfaye, K., Shimelis, B., Levine , S., et al. (2011). Preparing for The Future?
Understanding the Influence of Development Interventions on Adaptive Capacity at Local Level in
Ethiopia. Addis Ababa: ACCRA.
Masripatin, N. (2012). Penanganan Penyebab Deforestasi dan Degradasi Hutan dalam Implementasi REDD+ :
Mandat Internasional dan Kepentingan Nasional. Identification of Deforestation and Forest Degradation
Drivers and Activities that Result in Reduced Emissions, Increased Removals, and Stabilization of Forest
Carbon Stocks (hal. 17). Ambon dan Banjarmasin: Pusat Standarisasi dan Lingkungan, Kemenhut dan
Forest Carbon Partnership Facility-World Bank.
Perpres Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Silalahi, Urban. (2009). Metode Penelitian Sosial. Bandung: Rafika Aditama.
Spearman, M., & McGray, H. (2011). Making Adaptation Count : Concepts and Options for Monitoring and
Evaluation of Climate Change Adaptation. Germany: GIZ.