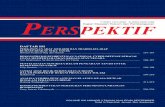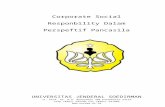Print this article - PERSPEKTIF
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Print this article - PERSPEKTIF
735
PERSPEKTIF, 11 (2) (2022): 735-744
DOI: 10.31289/perspektif.v11i2.6233
PERSPEKTIF
Available online http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif
Peran Pimpinan Sumber Daya Manusia Menjadi Leader Dalam Penegakan Etika Anti Diskriminatif
The Role of Human Resources Leaders Become Leaders in
Enforcement of Anti-Discriminatory Ethics
Tri Agus Saputra* & Chandra Wijaya
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Indonesia
Diterima: 02 Desember 2021; Direview: 04 Desember 2021; Disetujui: 02 Januari 2022
Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk melihat peran penting etika anti-diskriminatif serta peran manajer sumber daya manusia sebagai pilar utama penegakan etika anti-diskriminatif. Diskriminasi merupakan salah satu jenis permasalahan etik yang muncul dalam bidang ketenagakerjaan. Tugas untuk penghapusan tindakan diskriminatif secara umum menjadi tanggung jawab negara, namun demikian pada prakteknya banyak kasus-kasus diskriminatif yang terjadi justru tidak terjangkau oleh negara sehingga pada akhirnya memerlukan peran aktif dari entitas di luar struktur kenegaraan untuk dapat menjadi garda terdepan dalam penyelesaian permasalahan diskriminatif. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur. Data-data didapatkan dan dikumpulkan dari analisis dokumen berupa buku, artikel publikasi dan peraturan pemerintah. Kajian ini menyimpulkan bahwa manajer sumber daya manusia dianggap sebagai entitas yang paling dekat dan cocok dalam ranah pengelolaan etik karena manajer sumber daya manusia adalah entitas yang sangat dekat dan berhadapan langsung dengan manusia dalam sebuah organisasi. Ketika berbicara etika maka akan sangat terkait erat dengan hubungan antar manusia dan hubungan antara manusia dengan organisasi Kata Kunci: Kesetaraan; Organisasi; Sumber Daya Manusia; Kode Etik; Diskriminasi.
Abstract
This article aims to look at the important role of anti-discriminatory ethics and the role of human resource managers as the main pillars of anti-discriminatory ethics enforcement. Discrimination is one type of ethical problem that arises in the field of employment. The task of eliminating discriminatory actions is generally the responsibility of the state, however, in practice many discriminatory cases that occur are not reached by the state so that in the end it requires an active role from entities outside the state structure to be at the forefront of resolving discriminatory problems. The method used in this study is a qualitative method with a qualitative descriptive approach through literature study. The data obtained and collected from the analysis of documents in the form of books, articles and government regulations. This study concludes that human resource managers are considered the closest and most suitable entity in the realm of ethical management because human resource managers are entities that are very close and face to face with humans in an organization. When talking about ethics, it will be very closely related to the relationship between humans and the relationship between humans and organizations. Keywords: Equality; Organization; Human Resources; Ethic Code; Discrimination. How to Cite: Saputra, T.A., & Wijaya, W., (2022), Peran Pimpinan Sumber Daya Manusia Menjadi Leader Dalam Penegakan Etika Anti Diskriminatif, PERSPEKTIF, 11 (2): 735-744
*Corresponding author: E-mail: [email protected]
ISSN 2085-0328 (Print) ISSN 2541-5913 (online)
Tri Agus Saputra & Chandra Wijaya, Peran Pimpinan Sumber Daya Manusia Menjadi Leader
736
PENDAHULUAN Diskusi mengenai tata kelola organisasi
dan penegakan etik selalu menjadi tema diskusi yang menarik baik di media maupun dalam kajian akademis (Bennington, 2007). Banyak organisasi yang telah secara terstruktur membangun kode etik dalam organisasinya, khususnya pada sebagian besar organisasi publik. Namun demikian banyak juga organisasi pada sektor privat yang juga telah secara gradual menjadikan etik sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas bisnisnya.
Kode etik telah berkembang menuju ke arah penyempurnaan peran sebagai bagian penting dari sebuah organisasi. Tidak sedikit sebagian organisasi privat atau organisasi publik hancur karena bukan hanya tidak comply kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku umum, namun mereka justru tidak mematuhi kode etik yang mereka buat sendiri (Meisinger, 2002).
Banyak pihak beranggapan bahwa penegakan etika sangatlah penting dalam berjalannya sebuah organisasi. Namun pada saat yang bersamaan muncul ketidakjelasan dan kebingungan siapa yang paling bertanggungjawab dan berwenang dalam mengawal dan menegakkan etika dalam sebuah organisasi.
Ulrich (2001) melalui teorinya the role of human resources unit mengatakan salah satu peran unit sumber daya manusia adalah sebagai change agent atau agen perubahan. Dimana salah satu perannya adalah menjadi mitra strategis organisasi tidak hanya dari aspek bisnis tetapi juga dari aspek lain yang salah satunya adalah penegakan etika di dalam organisasi.
Artikel ini bertujuan membahas peran dan tanggung jawab manajer sumber daya manusia dalam pengelolaan etika di dalam organisasi. Manajer sumber daya manusia sering dianggap sebagai pihak atau entitas yang paling tepat dalam menegakkan etika organisasi karena manajer sumber daya manusia adalah lini manajer yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan subyek etik yaitu karyawan itu sendiri.
Peran manajer sumber daya manusia tidak lagi dilihat sebagai peran yang bersifat administratif tetapi sudah beralih kepada peran-peran yang lebih strategis dalam penegakan etika anti diskriminatif.
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Creswell (2016) mendeskripsikan penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang menempatkan peneliti sebagai instrumen utama penelitian. Penelitian kualitatif terdiri dari seperangkat praktik utama yang bersifat interpretatif yang membuat permasalahan jelas terlihat.
Peneliti melakukan studi pustaka terhadap berbagai publikasi, majalah, artikel dan berita terkait peran pimpinan sumber daya manusia dalam organisasi serta fungsi dalam penegakan etika anti-diskriminatif.
Pada tahap analisis, penelitian tidak melakukan pembuktian konsep atau membandingkan teori dengan hasil lapangan. Kajian ini mendeskripsikan konsep peran pimpinan sumber daya manusia dalam menjaga dan mengembangkan peran sebagai pemimpin dalam penegakan etika anti-diskriminatif di lingkungan kerja. HASIL DAN PEMBAHASAN
Seperti diungkapkan dalam pendahuluan, bahwa artikel ini bertujuan untuk membahas peran dan tanggung jawab manajer sumber daya manusia dalam mengelola etika di dalam organisasi khususnya dalam mengawal dan menjaga etika anti-diskriminatif di lingkungan kerja. Dalam artikel ini juga akan dibahas sejauh mana elaborasi etika anti-diskriminatif di sektor pemerintahan terutama dalam tata kelola aparatur sipil negara.
Manajer sumber daya manusia ditantang tidak hanya mampu dalam membangun kompetensi sumber daya manusia tetapi juga mampu membangun kapasitas sumber daya yang dimiliki menjadi sumber daya manusia yang memahami dan menghargai nilai serta etika. Memiliki kesempatan kerja yang setara (equal employment opportunity/EEO) merupakan pelaksanaan dari hak asasi manusia yang paling dasar dan hal tersebut juga menjadi permasalahan serius dalam pengelolaan sumber daya manusia (Cascio & Boudreau, 2016). Karena sifatnya yang sangat mendasar maka EEO sudah diadopsi di banyak negara dan juga telah menjadi isu penting pada organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) (Florini, 2003).
PERSPEKTIF, 11 (2) (2022): 735-744
737
Banyak kasus dalam dunia tenaga kerja yang dipengaruhi oleh adanya pelanggaran EEO, terutama terjadi di Amerika Serikat. Diantara jenis pelanggaran EEO yang terjadi adalah terkait dengan rekrutmen dan seleksi dan hal tersebut menjadi bobot yang paling besar terjadi pelanggaran karena tidak adanya transparansi dalam prosesnya. Di sebagian negara-negara barat maupun negara non-barat kejadian diskriminasi dalam pekerjaan merupakan hal yang biasa terjadi (Bennington, 2007). Namun demikian menurut (Martin & Woldring, 2001) bahwa perlindungan terhadap kesetaraan dalam kesempatan kerja adalah termasuk masalah hukum dan etika sehingga setiap negara sudah semestinya memiliki perangkat hukum dan etika anti-diskriminasi serta melakukan edukasi kepada warga negaranya.
Dalam perjalanannya, menurut (Dickens, 1999) adanya undang-undang dan perangkat hukum serta etika anti-diskriminasi belumlah cukup. Permasalahan diskriminasi dalam pekerjaan masih tetap ada dan muncul kekhawatiran bahwa dalam pelaksanaan EEO mengakibatkan perubahan negatif pada sektor publik dalam sebuah negara yang mana seharusnya sektor publiklah yang menjadi panduan dalam penerapan kebijakan dan kepatuhan terhadap undang-undang tentang EEO. Namun demikian dengan adanya reformasi manajemen sektor publik yang dikenal dengan new public management (NPM) dimana sektor publik berubah bentuk menjadi model swasta (Hughes, 1998) telah menimbulkan potensi terabaikannya penerapan EEO. Hal tersebut terjadi dalam bentuk pelimpahan model manajemen sumber daya manusia ke arah pengalihan sumber daya (outsourcing) daripada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tetap. Selain itu, konsep new public management juga mengalihkan pendekatan dari yang tadinya pendekatan berbasis regulasi/aturan untuk sektor publik menjadi pendekatan yang menekankan kepada hasil/output.
Kellough (1999) menyatakan bahwa kontrol terhadap konsistensi, keadilan dan kesetaraan dalam sistem kepegawaian telah hancur akibat adanya perubahan paradigma sektor publik yang mengakibatkan adanya perubahan dalam pola manajemen sumber
daya manusia. Masalah-masalah seperti itu tidak lepas dari lemahnya institusi sektor publik serta rendahnya kualitas legislasi sehingga mengakibatkan tidak berjalannya penegakan hukum terhadap pelanggaran atas kebijakan EEO (Bertok 1999).
Dalam ranah kebijakan EEO, terdapat alasan kurangnya ketaatan terhadap kebijakan tersebut. Setidaknya ada dua alasan mengapa hal tersebut dapat terjadi, yaitu: 1) pengusaha tidak terikat untuk tunduk pada legislasi EEO serta adanya pelanggaran secara terang-terangan terhadap undang-undang anti-diskriminasi yang terjadi pada beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada dan Selandia Baru (Harcourt and Harcourt 2002), 2) keterlibatan konsultan rekrutmen yang melakukan pekerjaan rekrutmen lintas sektoral tidak secara universal mematuhi undang-undang tentang EEO (Bennington, 2007) yang menyebabkan para pencari kerja dan karyawan tidak dapat melindungi diri mereka sendiri.
Tidak menutup kemungkinan pelaksanaan EEO tidak hanya digawangi oleh manajer sumber daya manusia atau tingkat manajer lini yang lain tetapi juga memerlukan pengaruh positif dari organisasi lain seperti gereja dan serikat pekerja. Gereja dan serikat buruh memiliki peran penting dan signifikan dalam perkembangan EEO, meskipun dalam kenyataannya masih terdapat perbedaan pendapat diantara para pemuka gereja tentang peran wanita dalam EEO yang masih diragukan. Begitu juga dengan keberadaan serikat pekerja, walau memiliki peran yang lebih kompleks, serikat pekerja seringkali juga dianggap bagian dari adanya diskriminasi pekerjaan. Serikat pekerja sering dianggap memainkan dualisme peran, satu sisi mendukung para pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya, namun di sisi yang lain banyak serikat pekerja justru menjadi bagian dari manajemen sehingga menimbulkan kesan bahwa serikat pekerja hanya kepanjangan tangan dari pengusaha.
Sebagai salah satu lini manajemen dalam organisasi, peran unit sumber daya manusia semakin signifikan dan bernilai mengingat selain mengelola sumber daya manusia, peran unit sumber daya manusia juga lebih strategis dengan adanya tugas dalam pengelolaan etik.
Tri Agus Saputra & Chandra Wijaya, Peran Pimpinan Sumber Daya Manusia Menjadi Leader
738
Pendekatan manajemen sumber daya manusia di Inggris dan Amerika Serikat dalam beberapa dekade terakhir telah menunjukkan bahwa lebih menghargai peran EEO sebagai salah satu pilar yang harus menjadi mainstream dalam manajemen sumber daya manusia. Sebagai contoh bahwa dengan penerapan paradigma EEO dalam perusahaan maka telah sesuai dengan paradigma bahwa unit sumber daya manusia menjadi change agent, meningkatkan value organisasi dengan meningkatnya persepsi keadilan, kemudahan dalam proses rekrutmen, peningkatan produktivitas karyawan serta kemudahan dalam pengambilan keputusan strategis organisasi. Selain itu, dengan menerapkan paradigma EEO juga memperkecil kemungkinan adanya tuntutan hukum kepada organisasi akibat isu diskriminasi.
Berbicara mengenai peran unit sumber daya manusia telah menjadi suatu hal yang sangat penting dan signifikan terutama dalam pembangunan budaya organisasi. (Ulrich and Beatty 2001) menjelaskan bahwa peran unit sumber daya manusia tidak lagi berada pada posisi yang tidak strategis, melainkan memiliki fungsi yang strategis untuk mendukung kinerja organisasi.
Ulrich menyebutkan peran unit sumber daya manusia sebagai The Role of HR dan membagi peran unit sumber daya manusia menjadi empat fungsi strategis, yaitu: Strategic partner (SP) yang merupakan fungsi sebagai penyelaras kegiatan dan inisiatif unit sumber daya manusia dengan strategi bisnis organisasi. Change agent (CA) menjadi fokus area yang sangat penting dari model Ulrich. Agen perubahan terkait dengan dukungan perubahan dan transisi bisnis di bidang sumber daya manusia dalam organisasi. Peran sumber daya manusia adalah mendukung kegiatan perubahan serta memastikan kapasitas untuk perubahan. Administrative expert (AE) merupakan fungsi yang selalu melekat dalam setiap proses bisnis sumber daya manusia. Pada awalnya AE hanya berfungsi memastikan kualitas layanan yang diberikan seoptimal mungkin, namun saat ini AE telah bertransformasi kepada kemungkinan untuk memberikan layanan berkualitas kepada organisasi yang fokus kepada efisiensi. Employee champion (EC) merupakan peran unit sumber daya manusia yang sangat signifikan dalam pengembangan tidak hanya aspek karir pegawai namun juga pada aspek-aspek lainnya.
Gambar 1. Ulrich Model of HR Roles
Unit sumber daya manusia adalah praktik
dengan potensi strategis yang signifikan untuk bisnis. Karena itu, banyak masalah dalam lingkungan sumber daya manusia saat ini ada yang memiliki pengaruh pada bagaimana hal itu diimplementasikan dengan baik, dimanfaatkan, dan diterima dalam dunia bisnis modern (Thoman and Lloyd 2018).
Peran unit sumber daya manusia telah berkembang sangat pesat dari masa ke masa. Sekuens yang dilalui juga menunjukkan bahwa fungsi unit sumber daya manusia menjadi unit
yang signifikan dalam mewujudkan sasaran organisasi. Peran sumber daya manusia mulai dari aspek administrasi unit sumber daya manusia hingga fungsi sumber daya manusia fungsional, melalui kemitraan strategis, konsep sumber daya manusia telah berkembang untuk mencerminkan cara organisasi memandang dan mengelola karyawan mereka selama proses pengembangan organisasi. Dalam organisasi yang secara tradisional berorientasi pada produksi, karyawan hanya dilihat sebagai roda penggerak perangkat yang dapat
Tri Agus Saputra & Chandra Wijaya, Peran Pimpinan Sumber Daya Manusia Menjadi Leader
dipertukarkan, hanya membutuhkan manajemen administratif tanpa dukungan signifikan lainnya (Tran 2015).
Dalam organisasi pembelajar, karyawan sekarang dilihat sebagai sumber daya yang harus memperoleh pengetahuan baru dan mengembangkan keterampilan baru untuk memajukan bisnis; oleh karena itu, mereka membutuhkan tingkat manajemen yang lebih fungsional dari departemen sumber daya manusia yang sebenarnya untuk memelihara pertumbuhan ini dan mengintegrasikan keterampilan ini ke dalam desain organisasi yang lebih besar. Terakhir, dalam pengembangan organisasi, unit sumber daya manusia dituntut untuk secara strategis mengintegrasikan pengembangan karir holistik setiap karyawan ke dalam misi dan rencana strategis organisasi secara keseluruhan.
Dengan peran sumber daya manusia seperti yang diungkapkan oleh Ulrich, maka terdapat potensi yang besar dalam penguatan paradigma EEO dalam organisasi karena diyakini bahwa fungsi ini bersifat inheren dalam menjujung tinggi nilai keadian yang diinginkan dalam organisasi. Unit sumber daya manusia selaku pemegang kendali dalam proses rekrutmen dan seleksi dapat secara terstruktur mengambil tanggung jawab dalam pelaksanaan EEO. Isu affirmative action (AA) dalam proses rekrutmen juga telah menjadi bagian penting dalam fungsi yang dijalankan oleh unit sumber daya manusia.
Peran unit sumber daya manusia dalam pelaksanaan EEO bukannya tanpa kritik. Banyak kritik yang menyebutkan bahwa peran yang diambil seharusnya bukan hanya sebagai mitra, namun didorong untuk mengambil peran lebih jauh sebagai pemain utama. Manajer sumber daya manusia perlu melakukan improvement dalam bentuk memberikan pelatihan, memimpin dan membangun serta memfasilitasi organisasi untuk menjadi nurani organisasi (Ulrich & Beatty, 2001). Manajer sumber daya manusia harus membentuk sebuah model perilaku yang diperlukan untuk semua manajer dalam tata kelola dan sumber daya manusia, memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia telah berjalan sesuai arah dan memastikan bahwa organisasi bermain sesuai aturan. Manajer sumber daya manusia harus memastikan terbangunnya budaya keterbukaan dan anti-diskriminasi dalam bisnis organisasi.
Muncul kritik yang lain bahwa peran unit sumber daya manusia masih jauh dari kejelasan pada sebagian besar organisasi (Gibb 2000). Peran dan persepsi staf sumber daya manusia terhadap pelaksanaan EEO belum memiliki keseragaman sehingga dalam pelaksanaannya tidak berjalan cukup baik. Sebagian ahli berpendapat bahwa unit sumber daya manusia peduli dengan nilai tambah organisasi, namun demikian cara yang digunakan seringkali dianggap tidak patut.
Manajer sumber daya manusia dianggap sebagai pihak yang tidak fleksibel dan terlalu kaku dalam menerapkan aturan, prosedur dan kebijakan. Oleh karenanya tidak heran jika dalam beberapa literatur dikatakan bahwa unit sumber daya manusia haruslah bersifat fleksibel mengikuti perkembangan, terutama terkait penegakan etik. Pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan apakah berarti bahwa unit sumber daya manusia harus memiliki etika yang fleksibel juga dan tidak khawatir tentang kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
Pelaksanaan EEO di Amerika Serikat terlihat lebih masif dan formil terbukti dengan adanya berbagai regulasi federal dan negara bagian yang melarang diskriminasi dalam pekerjaan, seperti undang-undang tentang hak sipil tahun 1964, undang-undang disabilitas, undang-undang pembayaran yang setara dan juga undang-undang ketenagakerjaan. Oleh karena itu dengan banyaknya regulasi yang mengatur anti-diskriminasi, organisasi diharapkan dapat membangun dan mempertahankan mekanisme kepatuhan internal mereka sendiri. Muncul pertanyaan bahwa dimana para karyawan yakin bahwa mereka telah diperlakukan secara diskriminatif atau tidak. Kemana para karyawan akan menyampaikan keluhan atas tindakan diskriminatif tersebut. Disinilah pentingnya membangun serta mempertahankan mekanisme kepatuhan internal sehingga permasalahan pelanggaran diskriminatif dapat segera ditindaklanjuti.
Dalam regulasi anti-diskriminasi di Amerika Serikat juga di atur mengenai whistle-blowing system (WBS). Praktek WBS di Amerika Serikat telah berjalan dalam kurun waktu yang lama. WBS di Amerika Serikat dilindungi oleh undang-undang. Dalam konteks perusahaan, pelaku whistle-blower dilindungi dari pembalasan atau viktimisasi oleh
739
PERSPEKTIF, 11 (2) (2022): 735-744
manajemen. Sebagai contoh dalam undang-undang hak asasi manusia Amerika Serikat tahun 1964 bagian VII melarang dua bentuk pembalasan, yaitu: pertama, pembalasan oposisi yang terjadi akibat dari seorang karyawan yang menentang praktek yang melanggar hukum dengan menyampaikan keberatan kepada manajemen perusahaan yang secara eksplisit tindakan tersebut menyatakan bahwa perilaku atau praktek tersebut merupakan suatu bentuk diskriminasi pekerjaan dan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Kedua, jenis pembalasan yang timbul akibat karyawan terlibat dan memberikan bantuan dalam sebuah penyelidikan kasus diantaranya dengan menjadi saksi, membiayai penyelidikan.
Dalam pelaksanaan EEO, hal yang umum bila pengusaha mendelegasikan banyak tanggung jawab untuk kepatuhan kepada manajer EEO yang bertugas pada unit sumber daya manusia ataupun unit yang bersifat khusus. Dalam kode etik federal disebutkan bahwa unit EEO memiliki tugas untuk menyusun program affirmative action, teknik komunikasi internal dan eksternal, membantu mengidentifikasi masalah, merancang dan menetapkan sistem audit dan pelaporan untuk memastikan efektivitas program, serta membangun fungsi sebagai jembatan antar organisasi dan antara organisasi dengan lembaga penegak hukum. Selain itu peran lain yang juga sangat penting adalah menjadi penghubung antara organisasi dengan kelompok minoritas yang diantaranya terdiri dari perempuan dan kaum minoritas.
Weatherspoon melaporkan bahwa uraian pekerjaan tersebut adalah uraian pekerjaan yang khas yang bagi karyawan yang bekerja di unit EEO. Tugas lain yang tidak kalah penting adalah merekomendasikan tindakan indisipliner bagi karyawan yang melanggara undang-undang dan kebijakan anti-diskriminasi serta untuk mengingatkan masyarakat dan badan-badan pemerintah terkait terhadap adanya praktek diskriminatif.
Contoh kasus di Amerika yang cukup menarik perhatian publik adalah apa yang terjadi dengan Becky Clark. Ia mendapati suaminya yang bekerja pada perusahaan yang sama menemukan kebijakan pembayaran yang sangat rahasia. Padahal ia melakukan hal yang
sama dengan yang dilakukan suaminya. Lalu kemudian ia protes atas pemberian gaji yang tidak sama untuk dirinya dan mengancam akan melaporkan kepada otoritas terkait. Hal tersebut dilakukannya di depan karyawan lain dan atasannya. Becky Clark akhirnya meninggalkan tempat kerja dan tidak bekerja lembur sesuai kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Perusahaan akhirnya memberhentikan Becky Clark. Kasus ini kemudian bergulir terus sampai ke tingkat pengadilan yang pada akhirnya pengadilan memutuskan untuk memenangkan perusahaan karena Becky Clark dianggap tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Yang menarik, pengadilan juga memutuskan bahwa seharusnya Becky Clark menyampaikan keluhannya secara pribadi kepada pihak yang berwenang daripada di depan karyawan lain atau bahkan pihak eksternal. Kasus ini menunjukkan bahwa orang awam memiliki pengetahuan yang terbatas tentang diskriminasi yang mengakibatkan adanya potensi penindasan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki.
Kasus kedua yaitu mengenai staf pada sebuah perusahaan dimana staf tersebut menyampaikan keluhan kepada atasan tentang diskriminasi ras namun tidak mendapatkan respon yang baik sehingga akhirnya dilakukan “eskalasi” kepada pejabat diatas yang lebih tinggi. Peristiwa tersebut mengakibatkan staf tersebut diberhentikan dari pekerjaannya. Atas kasus tersebut pengadilan memutuskan memenangkan karyawan dengan alasan bahwa perusahaan harus ada keseimbangan antara hak karyawan untuk menyuarakan keluhan kepada majikan dalam menjalankan bisnisnya.
Isu loyalitas kepada perusahaan disebut sebagai tugas yang paling utama bagi karyawan. Namun seperti diungkapkan (Pfeiffer 1992), kesetiaan merupakan konteks spesifik dan konsep relatif. Dengan melaporkan perilaku diskriminatif maka hal tersebut merupakan upaya terbaik serta menjadi hal yang paling etis dan legal untuk dilakukan.
Konsepsi mengenai EEO pada dasarnya telah terserap di dalam Konstitusi Republik Indonesia pasal 28D yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama dihadapan hukum.
740
Tri Agus Saputra & Chandra Wijaya, Peran Pimpinan Sumber Daya Manusia Menjadi Leader
Selain itu negara juga menjamin setiap orang untuk bekerja serta mandapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja serta memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam proses bernegara di Indonesia dan menjadi poros utama dalam kehidupan tata kelola pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden dan Wakil Presiden sebagai pucuk pimpinan tertinggi yang menjalankan peran sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan sudah semestinya membuat produk-produk hukum yang mengafirmasi nilai-nilai utama dalam Konstitusi Republik Indonesia.
Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah berupaya membangun core value atau nilai inti dari aparatur sipil negara. Dalam Undang-undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara dibangun dengan asas-asas: (1) kepastian hukum; (2) profesionalitas; (3) proporsionalitas; (4) keterpaduan; (5) delegasi; (6) netralitas; (7) akuntabilitas; (8) efektif dan efisien; (9) keterbukaan; (10) non-diskriminatif; (11) persatuan dan kesatuan; (12) keadilan dan kesetaraan; dan (13) kesejahteraan.
Lebih lanjut dalam penjelasan beleid dimaksud disebutkan bahwa asas non-diskriminatif dimaknai dengan tidak menciptakan perbedaan perlakuan berbasis jender, suku, ras, golongan dan agama dalam penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara khususnya dalam menjalankan fungsi aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara harus mengedepankan asas transparansi dan non-diskriminatif sejak dari proses rekrutmen dan seleksi, penempatan, pengembangan sampai pada fase terminasi.
Permasalahan yang sering muncul adalah terkait ketersediaan formasi bagi penyandang disabilitas untuk dapat direkrut menjadi aparatur sipil negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai
Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 disebutkan bahwa dalam pengadaan aparatur sipil negara instansi pusat dan daerah wajib mengalokasikan formasi/jabatan yang bisa dilamar oleh penyandang disabilitas paling kurang sebanyak 2 (dua) persen dari formasi yang ditetapkan untuk instansinya. Dalam prakteknya tidak banyak instansi yang dapat memenuhi kuota tersebut mengingat lemahnya perencanaan instansi pusat dan daerah dalam hal menyusun persyaratan jabatan dan uraian jabatan yang sesuai untuk penyandang disabilitas.
Muchtar et al. (2020) melakukan penelitian tentang evaluasi penerimaan penerimaan calon pegawai negeri sipil di Kalimantan Selatan tahun 2018. Beberapa kelemahan mengemuka berdasarkan hasil penelitian tersebut, yaitu: (1) kurangnya sumber informasi data terbaru terkait informasi jumlah dan kondisi penyandang disabilitas (pendidikan dan jenis disabilitas) di Provinisi Kalimantan Selatan; (2) kurangnya persiapan waktu yang relatif singkat dalam mempersiapkan dan kurang berpengalamannya panitia seleksi khususnya untuk menyeleksi penyandang disabilitas; (3) terdapat pemahaman dan penafsiran yang berbeda antara instansi pusat dan instansi daerah; (4) proses perencanaan kurang mengedepankan pendekatan partisipatif; (5) belum disusunnya prosedur operasi baku terkait seleksi penyandang disabilitas; (6) tidak disediakannya akses yang terbuka untuk informasi dan pengaduan dalam seleksi penyandang disabilitas.
Problematika lain yang muncul adalah terkait pemilihan formasi jabatan serta unit kerja penempatan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Penetapan jenis dan derajat disabilitas juga menjadi persoalan ketika penyandang disabilitas merasa perlu diafirmasi hak-haknya oleh negara sesuai dengan pasal 28D dalam Konstitusi Republik Indonesia. Hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah sejauh mana kesiapan sarana prasarana/aksesibilitas pada masing-masing instansi pusat maupun daerah untuk dapat merekrut penyandang disabilitas.
Profesi aparatur sipil negara selain memiliki tiga fungsi utama sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat serta pemersatu bangsa juga memiliki 15 (lima
741
PERSPEKTIF, 11 (2) (2022): 735-744
belas) nilai dasar yang harus melekat dalam setiap diri aparatur sipil negara. Kelima belas nilai dasar tersebut adalah: (a) memegang teguh ideologi Pancasila; (b) setia dan mempertahankan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pemerintahan yang sah; (c) mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia; (d) menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; (e) membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; (f) menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif; (g) memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur; (h) mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik; (i) memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah; (j) memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, tepat, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun; (k) mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi; (l) menghargai komunikasi, konsultasi dan Kerjasama; (m) mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai; (n) mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; (o) meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.
Rumusan nilai dasar tersebut kemudian mengalami kristalisasi menjadi Tujuh Nilai Inti Aparatur Sipil Negara yang dikenal dengan akronim BerAKHLAK. BerAKHLAK memiliki makna (1) Berorientasi Pelayanan; (2) Akuntabel; (3) Kompeten; (4) Harmonis; (5) Loyal; (6) Adaptif; (7) Kolaboratif.
Presiden Joko Widodo dalam sambutan peluncuran core values ASN BerAKHLAK pada 27 Juli 2021 mengatakan bahwa setiap individu aparatur sipil negara dimanapun bertugas seharusnya memegang teguh nilai dasar dan semboyan yang sama. Seluruh aparatur sipil negara dari berbagai profesi seperti dosen, guru, jaksa, dokter, perawat, analis kebijakan, administrator mapun petugas satuan polisi pamong praja di tingkat pusat dan daerah harus memiliki nilai dasar dan proposisi nilai yang sama (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 27 Juli 2021).
Lebih lanjut Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa menjadi aparatur sipil negara dihadapkan pada tantangan disrupsi dalam berbagai bidang sehingga perlu
dilakukan akselerasi untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam menghadapi era disrupsi yang semakin masif. Upaya kolaboratif dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu terus ditingkatkan baik yang bersifat lintas organisasi, lintas daerah, lintas keilmuan dan juga lintas profesi. Saat ini dunia telah berkembang menjadi serba hybrid, serba kolaboratif sehingga tidak boleh ada ego sektoral, ego daerah dan ego kelimuan.
Dalam kaitan tersebut salah satu nilai dari tujuh nilai dasar aparatur sipil negara yaitu “harmonis” menjadi penting dalam membentuk karakter aparatur sipil negara yang lebih humanis karena merupakan perwujudan dari penegakan nilai-nilai anti-diskriminatif. Dalam nilai harmonis terkandung sub nilai: (1) menghargai setiap orang apapun latar belakangnya; (2) suka menolong orang lain; (3) membangun lingkungan kerja yang kondusif.
Membangun lingkungan kerja yang kondusif bukan pekerjaan yang mudah, tetapi juga tidak sulit tergantung bagaimana kita memberikan respon terhadap sebuah permasalahan di lingkungan kerja kita. Permasalahan diskriminasi di lingkungan kerja berawal dari tidak tepatnya pola kerja yang dibangun yang memiliki kecenderungan-kecenderungan tertentu terhadap obyek pekerjaan. Sebagai contoh yaitu diskriminasi berbasis jender dimana pegawai perempuan perlu upaya keras untuk membuktikan bahwa kemampuan yang dimiliki melebihi laki-laki. Contoh lain dalam lingkungan kerja adalah ketika supervisi dilakukan lebih ketat terhadap pegawai dengan suku, agama dan ras tertentu yang mengakibatkan timbulnya potensi konflik horizontal. Pegawai dengan tingkat senioritas tertentu biasanya sulit mendapat peran karena dianggap sudah terlalu tua sehingga timbul kesan lambat dan kurang akseleratif dan semangat. Di era yang serba terbuka saat ini, potensi bullying terhadap pegawai penyandang disabilitas juga sangat mungkin terjadi dan hal tersebut merupakan fakta yang tak terbantahkan. Selain itu, penilaian performa kerja dan opini yang tidak dihargai juga merupakan bentuk dari tindakan diskriminatif di lingkungan kerja.
Oleh karenanya sudah tepat bila apatur sipil negara dibentuk dan dibangun dengan nilai-nilai “harmonis’ yang merupakan
742
Tri Agus Saputra & Chandra Wijaya, Peran Pimpinan Sumber Daya Manusia Menjadi Leader
manifestasi dari nilai-nilai anti-diskriminatif yang sekaligus menjadi perekat dan pemersatu bangsa untuk menghindarkan munculnya potensi konflik yang akan membuat lingkungan kerja semakin kontra-produktif.
Untuk memastikan bahwa paradigma EEO telah dilakukan dengan tepat, perlu dilakukan audit etik secara holistik. Kegiatan audit etik jarang dilakukan karena merupakan hal yang sangat sensitif, terutama terkait dengan obyek audit mengenai anti-diskriminatif.
Salah satu alternatif yang bisa ditempuh untuk menjamin agar audit etik tetap dapat dilakukan adalah dengan menggunakan auditor eksternal. Auditor eksternal akan lebih independen dan netral dalam melihat serta menilai sebuah permasalahan dalam organisasi. Audit juga berguna untuk memastikan bahwa peran manajemen telah sesuai pada porsinya dan telah patuh pada peraturan perundangan.
Audit kepatuhan Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah perusahaan yang diaudit mematuhi prosedur, aturan, atau peraturan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi (A. Arens, Randal, and Beasley 2012). Audit kepatuhan biasa terjadi pada sektor publik atau pemerintahan.
Meskipun demikian, audit eksternal perlu dilakukan secara hati-hati, mengingat objek audit yang sangat sensitif. Banyak kejadian-kejadian diskriminatif yang terjadi dalam organisasi luput dari catatan bagi auditor eksternal (Florini, 2003). Auditor eksternal cenderung berpendapat bahwa kegiatan tersebut tidak cukup memiliki manfaat sehingga tidak layak untuk menjadi bahan temuan. Apabila terjadi demikian maka akan sulit bagi organisasi untuk melakukan pembenahan dan improvement di internal organisasinya SIMPULAN
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa manajer sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dan signifikan dalam penegakan etika anti-diskriminatif. Selain itu penulis juga menemukan bahwa kode etik merupakan sebuah pernyataan yang secara khusus merujuk pada adanya kewajiban mematuhi hukum yang berlaku. Paradigma equal employement opportunity harus dijadikan
sebagai paradigma utama dalam organisasi terutama pada organisasi sektor publik untuk menghindari adanya diskriminasi dalam interaksi pekerjaan. Dalam membangun lingkungan pekerjaan yang kondusif manajer sumber daya manusia sudah selayaknya mengambil peran lebih dan menjadi agen bagi negara dalam membangun budaya anti-diskriminatif baik di internal maupun di eksternal organisasi. Dalam menjalankan fungsi sebagai pengawal paradigma equal employement opportunity, manajer sumber daya manusia perlu diletakkan pada posisi yang independen sehingga memiliki pandangan yang netral menilai dan memutuskan sebuah kasus etik. Untuk menjamin dan memastikan bahwa paradigma equal employement opportunity telah dijadikan kebijakan dan diimplementasikan, perlu dilakukan audit kepatuhan (compliance audit) bagi lembaga sektor publik secara berkala. Audit kepatuhan juga diperlukan untuk memastikan nilai-nilai inti organisasi benar-benar diterapkan dan menjadi bagian dari budaya organisasi.
DAFTAR PUSTAKA Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2012).
Auditing and assurance services: An Integrated Approach (Fourtheenth Edition).
Bennington, L. (2007). HR managers as ethics agents of the state. Human resource management: Ethics and employment, 137.
Bertok, J. (1999). OECD Supports the Creation of Sound Ethics Infrastructure: OECD1 Targets Both the “Supply Side” and the “Demand Side” of Corruption. Public Personnel Management, 28(4), 673-687.
Caldwell, R. (2003). Models of change agency: a fourfold classification. British Journal of Management, 14(2), 131-142..
Cascio, W. F., & Boudreau, J. W. (2016). The search for global competence: From international HR to talent management. Journal of World Business, 51(1), 103–114. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2015.10.002
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications.
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). The Sage handbook of qualitative research. sage.
Dickens, L. (1999). Beyond the business case: approach to equality action. Human Resource Management Journal, 9(1), 9–19.
Demuijnck, G. (2009). Non-discrimination in human resources management as a moral obligation. Journal of Business Ethics, 88(1), 83-101.
743
PERSPEKTIF, 11 (2) (2022): 735-744
Elizur, D., Borg, I., Hunt, R., & Beck, I. M. (1991). The structure of work values: A cross cultural comparison. Journal of Organizational Behavior, 12(1), 21-38.
Florini, A. (2003). Business and Global Governance - The Growing Role of Corporate Codes of Conduct. The Brookings Review, 21(2), 4–8.
Gibb, S. (2000). Evaluating HRM effectiveness: the stereotype connection. Employee Relations.
Harcourt, S., & Harcourt, M. (2002). Do employers comply with civil/human rights legislation? New evidence from New Zealand job application forms. Journal of Business Ethics, 35(3), 205-221.
Kardinah Indrianna Meutia, K. I. M., & Cahyadi Husadha, C. H. (2019). Pengaruh budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB), 4(1), 119-126.
Kellough, J. E. (1999). Reinventing public personnel management: Ethical implications for managers and public personnel systems. Public Personnel Management, 28(4), 655-671.
Lunenburg, F. C. (2010). Managing change: The role of the change agent. International journal of management, business, and administration, 13(1), 1-6.
Martin, G., & Woldring, K. (2001). Ready for the mantle? Australian human resource managers as stewards of ethics. International Journal of Human Resource Management, 12(2), 243–255. https://doi.org/10.1080/713769609
Meisinger, S. (2002). Trust in the Top, HR Magazine, 47(10): 8.
Muchtar, M., Nisa, L. S., & Siska, D. (2020). Evaluasi Penerimaan CPNS bagi Penyandang Disabilitas di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Kebijakan Pembangunan, 15(2), 203-217.
Pfeiffer, R. S. (1992). Owing loyalty to one's employer. Journal of Business Ethics, 11(7), 535-543.
Thoman, D., & Lloyd, R. (2018). A review of the literature on human resource development: Leveraging HR as strategic partner in the high performance organization. Journal of International & Interdisciplinary Business Research, 5(1), 147-160.
Tran, H. (2015). Personnel vs. strategic human resource management in public education. Management in Education, 29(3), 112-118.
Ulrich, D., & Beatty, D. (2001). From partners to players: Extending the HR playing field. Human Resource Management: Published in Cooperation with the School of Business Administration, The University of Michigan and in alliance with the Society of Human Resources Management, 40(4), 293-307.
Villegas, S., Lloyd, R. A., Tritt, A., & Vengrouskie, E. F. (2019). Human resources as ethical gatekeepers: Hiring ethics and employee selection. Journal of Leadership, Accountability and Ethics, 16(2), 80-88.Peraturan:
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019
Internet: Peluncuran Core Values dan Employer Branding
ASN, 27 Juli 2021, https://www.menpan.go.id/site/berita-foto/peluncuran-core-values-dan-employer-branding-asn
Peluncuran Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara, 27 Juli 2021, dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, https://setkab.go.id/peluncuran-core-values-dan-employer-branding-aparatur-sipil-negara-27-juli-2021-dari-istana-kepresidenan-bogor-provinsi-jawa-barat/
744