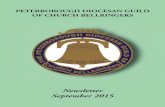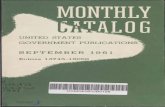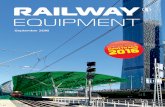PERISTIWA 24 SEPTEMBER 2011
-
Upload
cafe-acoustic -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of PERISTIWA 24 SEPTEMBER 2011
1
Peristiwa 24 September 2011
Di Buton Utara (Menggeledah Struktur dan Sebab-sebab Kekerasan Massa)
Nurlin1
(P1900212002)
Abstrak
Tulisan ini mengkaji tentang aksi dan kekerasan masa yang pernah terjadi di
Buton Utara tanggal 24 September 2011. Dalam peristiwa itu, 1 buah mobil
pemadam kebakaran, kantor DPRD Kabupaten Buton Utara dan Kantor
Bupati Buton Utara dibakar karena mejadi sasaran amukan masa. Landasan
teori dalam tulisan ini adalah teori tindakan kolektif Michael Bader,
struktural-fungsional Emile Durkheim, teori konflik Ralf Dahrendorf dan
teori agensi-struktur Anthony Giddens. Metodologi yang digunakan dalam
tulisan ini adalah metodologi kualitatif dengan menggunakan teknik
pengumpulan data melalui pengamatan dan kajian kepustakaan. Hasil
analisa menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi di Buton Utara tanggal
24 September 2011 merupakan gerakan massa yang dipersiapkan, tidak lahir
secara spontan, melainkan berasal dari adanya ketimpangan sosial yang
terpola akibat proses sosial-politik. Selain itu, disebabkan pula oleh adanya
kerapuhan struktur non-materil (sifat yang dibatinkan) masyarakat Buton
Utara.
Kata kunci: Aksi Sosial, Massa, dan Tindakan Kolektif,
1 Penulis adalah mahasiswa Program Pascasarjana Jurusan Antropologi
Universitas Hasanuddin
2
“tak ada yang lebih menakutkan manusia dari pada persentuhan dengan yang tidak dikenal”
Elias Canetti. Masa adalah pertama salinan kabur orang besar,
Kedua pembangkangan melawan orang besar, Ketiga, alat orang besar. Frederich Nietzsche.
Pengantar
Suasana yang mencekam terlihat diwajah kelompok massa saat
mereka mengetahui adanya makhluk buas ciptaan Dr. Frankestein dalam
Film Van Helsing. Kerumunan masa itu terlihat berani namun sebenarnya
mereka datang atas ketakutan mereka terhadap ancaman-ancaman
eksistensi ajaran-ajaran yang mereka anut. Masa tanpa peri kemanusiaan
membakar kediaman penelitian sang doktor. Tindakan yang tidak
sewajarnya itu menjadi hal yang mesti dilakukan sebab gerombolan
massa itu tak lagi melihat Frankestein sebagai manusia melainkan sebagai
sesuatu “yang lain” yang pantas dihancurkan.
Pengaburan konsep manusia dalam benak kepala massa membuat
wajah massa terlihat buas dan menakutkan. Teriakan-teriakan yang keluar
dari kerumunan massa itu menggambarkan betapa marahnya mereka
terhadap apa yang mereka benci. Segera setelah objek kebencian itu
bersentuhan langsung dihadapan massa, luapan emosi yang tak
terkendali membuat objek dalam hitungan menit berada dalam
cengkeraman “tangan massa”. Objek tak lagi dinilai sebagai mana dirinya
yang normal, melainkan dicitrakan sebagai sesuatu yang lain dan
abnormal. Praktek-praktek konsolidasi dalam hal mengadvokasi dan
menggerakan massa sangat berjasa dalam proses pecitraan suatu objek
sebagai yang abnormal, mejadi yang tidak semestinya ada dan harus
dihilangkan. Pencitraan objek ini menciptakan penafsiran yang negatif
dalam tafsiran massa. Melalui tafsiran negatif ini, massa menemukan
3
alasan-alasan kemarahannya dan mereduksi citra objek kemarahan dalam
kebencian-kebencian yang tak dapat ditoleransi. Dengan demikian,
bukanlah hal yang mengherankan apabila kita melihat sekumpulan massa
memukuli maling yang tertangkap di pasar, tidaklah menghrankan jika
tindakan massa begitu kejam ketika mengusir pengikut sekte atau aliran
agama Ahmadyah yang diaggap sesat, juga betapa kejamnya pengusiran
para warga terhadap orang yang dituduh sebagai dukun santet. Mereka
yang citranya telah terdeformasi dipandang bukan sebagai manusia lagi,
melainkan sebagai sesuatu yang menjijikan dan tidak pantas ada.
Luapan kemarahan massa yang membabi buta terjadi di Kabupaten
Buton Utara tangga 24 September 2011. Dalam kejadian itu, tak butuh
waktu lama, dua kantor milik pemerintah yakni kantor DPRD dan kantor
Bupati Buton Utara, beserta mobil pemadam kebakaran ludes terbakar
oleh massa yang mengatas namakan diri sebagai Penyelamat Undang-
Undang. Betapa pemerintah telah terdeformasi sebagai sasaran
kemarahan dan amukan massa. Entah apa kesalahan pemerintah dapat
dilihat dari nama massa yang terorganisir itu sebagai Penyelamat
Undang-Undang. Tentunya nama itu mengandaikan citra yang ditafsirkan
oleh massa yang sedang mengamuk. Citra itu megandaikan pemerintah
sebagai oknum yang tidak mengindahkan amanah Undang-Undang
Nomor 17 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara.
Citra pemeritah yang terdeformasi melalui penafsiran dalam kepala
massa menjadikan pemerintah sebagai bukan pemerintah melainkan
sebagai oknum yang melanggar Undang-Undang yang harus dilawan.
Gambaran inilah yang membuat monster berkepala banyak itu sangat
agresif melakukan pengrusakan tanpa kendali nilai sebagai sesama
manusia atau tanpa rasa hormat lagi terhadap pemerintah. Namun
persoalan kemudian adalah benarkah kesalahan pemerintah hanya
4
terletak pada sisi tafsiran Undang-Undang? Adakah penyebab lain yang
turut memengaruhi ledakan massa yang sangat destruktif itu?
Tulisan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Namun
penulis disini tidak bertujuan untuk membelah pemerintah, bukan pula
mencari kambing hitam, juga tidak memposisikan tulisan ini sebagai
naskah hukum atau naskah akademik pemecahan masalah. Tulisan ini
tidak lain adalah komentar akademik yang berupaya memahami dan
mengomentari sisi lain dari tindakan-tindakan masyarakat (tragedi 24
September) melalui kacamata teori-teori sosial.
Teori Struktural-Fungsionalisme dan Teori Konflik
Kedua teori ini dibahas bersama karena antara teori struktural-
fungsionalisme dan teori konflik tak dapat dipisahkan. Namun
bagaimanapun teori ini tidaklah berarti sama atau setara. Hanya saja teori
konflik merupakan pandangan lain atau antitesa dari teori strukturalisme-
fungsional. Kita akan mulai pembahasan mengenai teori Struktural-
Fungsional.
Struktural-fungsionalisme memandang masyarakat sebagai suatu
sebagai suatu sistem dari struktur-struktur sosial.2 Menurut Durkheim,
seorang individu terlahir dalam struktur yang telah mapan dan individu
tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti struktur tersebut. Durkheim
bahkan berpandangan bahwa pikiran dan pengalaman sekali pun
diwariskan.3 Artinya seorang individu dalam menghadapi fakta-fakta
sosial tidak dapat melakukan pilihan sendiri selain dari apa yang telah
2 Achmad Fedyani Saifuddin, Antropologi Kontemporer; Suatu Pengantar Kritis
Mengenai Paradigma (Ed. I, Cet. II, Jakarta, Kencana:2006) hlm. 156 3 PIP Jonas, Pengantar Teori-Teori Sosial; Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-
modernisme (Cet. II, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: 2010) hlm. 45
5
disediakan oleh budaya itu sendiri. Nama, kebiasaan suatu masyarakat
untuk tunduk kepada yang lebih tua, memakai baju, melaksanakan tugas
sebagai mahasiswa dan sebagai dosen semuanya telah diatur oleh
kebudayaan sebagai struktur itu sendiri dimana individu berada di
dalamnya tanpa punya pilihan lain selain mengikuti struktur itu.
Sedangkan struktur itu menurut Durkheim diwariskan melalui sosialisasi.
Struktur yang diwariskan itu menurut Durkheim berfungsi untuk
menjaga keteraturan sosial. Termasuk organisasi-organisasi sosial seperti
keluarga ada untuk menjalankan fungsinya di dalam struktur. Untuk
menjelaskan hal ini, Durkheim menggunakan analogi organik yang
merupakan karya Herbert Spencer. Dalam tubuh mahluk hidup terdapat
organ-organ yang memiliki fungsi masing-masing yang tak dapat
dipisahkan. Seperti otak sangat bergantung pada jantung yang memompa
darah dan keseluruhan sistem organ yang menjadi sayarat hidup mahluk
hidup. Rusaknya salah satu organ ini akan menyebabkan organisme itu
sakit. Demikian juga dengan masyarakat, jika salah satu organisasi sosial
sakit, akan mempengaruhi stabilitas masyarakat.4
Berbeda dengan teori strukturalisme-fungsional, teori konflik
melihat struktur dan fungsi yang ada dalam masyarakat sebagai bentuk
ruang-ruang penindasan. Ralf Dahrendorf membedakan antara teori
Struktural-Fungsionalisme:5 jika kaum fungsionalis menekankan pada
ketertiban masyarakat, para teoritis konflik melihat pertikaian dan konflik
ada pada setiap titik di dalam sistem sosial. Bagi kaum fungsionalis (atau
setidaknya kaum fungsionalis awal) berargumen bahwa setiap unsur di
dalam mayarakat menyumbang bagi stabilitas; maka para teoritis konflik
melihat bahwa banyak unsur masyarakat merupakan penyumbang
4 Lihat PIP Jonas, Ibid hal. 52
5 George Ritzer, Teori-Teori Sosial; Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan
Terkahir Post-modernisme (Cet. I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2012) hlm. 450
6
disintegrasi dan perubahan. Kaum Struktural-fungsionalis memandang
bahwa masyarakat diikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai,
dan moralitas bersama; para teoritis konflik melihat setiap ketertiban yang
ada di dalam masyarakat berasal dari pemaksaan sejumlah anggota
masyarakat oleh orang-orang yang berada di puncak dalam struktur.
Sementara kaum struktural-fungsionalis berfokus pada kohesi yang
diciptakan oleh nilai-nilai bersama masyarakat, para teoritis konflik
menekankan peran kekuasaan dalam memelihara tatanan di dalam
masyarakat.
Bagi penganut teori konflik, terdapat kesenjangan dalam struktur
sosial dimana ada kelompok yang diuntungkan oleh struktur dan
kelompok yang dirugikan oleh struktur. Mereka yang dirugikan
didominasi dengan sejumlah wacana dan otoritas kelompok yang
diuntungkan oleh struktur sosial yang berlaku. Selanjutnya Dahrendorf
mengatakan bahwa karena masyarakat itu berwajah dua (konflik dan
konsensus), maka masyarakat tidak bisa ada tanpa konflik dan konsensus
dan tidak bisa ada konflik jika tidak ada konsensus yang mendahuluinya.
Konsensus atau kesepakatan bersama yang diingkari dalam teori
konflik akan melahirkan konflik. Dengan demikian dalam kasus
kekerasan massa di Buton Utara berdasarkan pandangan teori konflik
dapat dikatakan bahwa peletakan ibu kota diluar amanah undang-undang
merupakan bentuk pengingkaran atas konsensus yang ditetapkan oleh
undang-undang. Tentunya pengingkaran ini dilakukan oleh kelompok
yang diuntungkan posisinya atau memiliki otoritas di dalam struktur
yakni pemerintah. Namun bagaimana kelompok yang dirugikan oleh
struktur ini menemukan artikulasi perlawanannya? Hal ini akan dibahas
didalam teori tindakan kolektif pada pembahasan selanjutnya.
7
Agensi dan Struktur (Teori Strukturasi)
Anthony Giddens adalah tokoh yang mempopulerkan teori
strukturasi. Jika Durkheim memandang struktur tak dapat berubah dan
ada sebelum manusia dilahirkan dan mempengaruhi seluruh tindakan
masyarakat, maka Giddens berpandangan lain. Menurut Giddens antara
struktur dan tindakan individu (Giddens menyebutnya sebagai Agensi)
keduanya tidak dapat dipisahkan: agensi tersirat didalam struktur dan
struktur tersirat dalam agensi.6 Artinya bahwa individu dapat bertindak
memengaruhi dan menciptakan struktur baru sekali pun pada sisi yang
lain (pada saat yang sama) agen dipengaruhi oleh struktur lama.
Giddens juga menjelaskan konsep kuasa dan agensi dalam teori
strukturasi. Bahwa tidak hanya struktur makro yang memiliki kuasa,
tetapi juga struktus mikro memiliki kuasa untuk mengubah struktur
makro. Giddens mengatakan bahwa adanya struktur yang membatasi
pilihan dalam bertindak tidak boleh diartikan dengan terputusnya
tindakan.7 Tidak memiliki pilihan bukan berarti seorang individu tidak
dapat bertindak. Individu dapat bertindak dengan kuasa kehendak yang
dimilikinya. Dalam pengertian ini, kuasa tidak diartikan sebagai
kepemilikan otoritas suatu kelompok masyarakat atau sejenis prilaku
khusus melainkan mencangkup seluruh tindakan, dan kekuasaan
bukanlah sumber daya. Sumber daya-sumber daya justru adalah sarana
untuk menjalankan kekuasaan sebagai unsur rutin instansiasi prilaku
dalam reproduksi sosial.8 Dengan demikian kekuasaan mencangkup
kontinuitas rutinisasi relasi kemandirian dan ketergantungan disepanjang
ruang dan waktu tindakan sosial. Semua bentuk ketergantungan memberi
6 George Ritzer, Ibid, hlm. 380
7 Anthony Giddens, Teori Strukturasi; Dasar-dasar Pembentukan Struktus Sosial
Masyarakat (Cet. I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2010) hlm. 23 8 Ibid, hlm. 25
8
sumber daya kepada bawahan untuk dapat memengaruhi atasannya.
Inilah yang disebut Giddens sebagai dialectic of control (dialektika kontrol).
Tak hanya atasan yang dapat mengontrol, namum mekanisme
ketergantungan atasan kepada bawahan dapat menjadi kuasa bawahan
untuk memengaruhi aktifitas atasan mereka. Dengan demikian apa yang
disampaikan oleh teori konflik: dalam struktur ada kelompok yang
diuntungkan karena mendapat otoritas dari struktur itu, melalui analisis
agensi Giddens, secara fungsional kelompok yang dirugikan dapat
memiliki otoritas terhadap kelompok yang berada di atas struktur.
Kekuasaan yang sama juga dimiliki oleh massa pembela Undang-
Undang ketika mereka melakukan tindakan kepada pemerintah. Sebagai
kelompok yang dirugikan oleh struktur akhirnya bertindak sebagai agensi
untuk merubah atau mereproduksi struktur yang baru (menstrukturasi)
dalam penetapan ibu kota kabupaten Buton Utara.
Konsep Massa dan Aksi Sosial
Menalar tentang aksi sosial dan kekerasan massa yang terjadi di
Buton Utara, saya menggunakan analisis Aksi Sosial menurut Sidney
Tarrow yang dianggap cukup relevan dengan tema yang dibicarakan.
Menurut Sidney Tarrow 9 terdapat beberapa syarat utama agar suatu
gerakan disebut sebagai Aksi Soail yakni: Pertama, suatu protes yang
dilakukan oleh massa dapat disebut sebagai gerakan bila didalamnya ada
aktor-aktor yang mengorganisasikan diri dan memobilisasi massa. Sebuah
organisasi atau lebih didalam sebuah aksi adalah salah satu tanda penting
bahwa protes itu memang terorganisir. Ini dimaksudkan untuk
9Idris Rahim, Identitas Etno Religius Dalam Pembentukan Provinsi Gorontalo,
Disertasi, Program Pasca Sarjana, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2010, hlm. 33-34
9
membedakan dari suatu kumpulan massa dengan kerumunan massa
(crowd).
Kedua, pentingnya pemahaman mengenai gerakan yang terorganisir
disini adalah mengenai asumsi tentang eksistensi sang aktor sosial yang
mengelola segala bentuk ketidak puasan dan kekecewaan (grievances),
atau isu bersama, menjadi identitas dan solidaritas, bahkan ideologi. Ini
sangat penting karena sebuah gerakan butuh dukungan publik,
setidaknya kelompok-kelompok organisasi untuk bergabung dalam suatu
protes. Aktor-aktor yang bergerak untuk melawan selalu secara dinamis
merancang tindakan sedemikian rupa untuk menciptakan peluang politik
bagi mereka ketika berhadapan dengan lawan-lawannya.
Ketiga, ada lawan-lawan yang setidaknya merupakan bagian dari
kelompok yang terorganisir pula. Lawan itu dapat berasal dari Negara,
militer-militer atau pemerintah, penguasa, pengusaha besar atau
perusahaan-perusahaan, baik lawan–lawan pada tingkat sektoral maupun
nasional adalah bagian dari sebuah kekuatan yang tidak hanya memiliki
legitimasi menggunakan alat-alat represi. Ada represi dalam bentuk
sebuah produk keputusan kebijakan penguasa yang dipandang tidak
menguntungkan, tidak menciptakan partisipasi mereka sementara hal itu
berkaitan langsung dengan masa depan mereka.
Keempat, tindak protes selalu mencerminkan adanya sebuah siklus
proses perlawanan yang terorganisir (gagal maupun sukses) terhadap
kekuasaan selalu terjadi berulang-ulang.
Pandangan-pandangan Sidney Tarrow di atas memberikan batasan
pada konsep aksi sosial yang mungkin berbeda dengan aksi sosial yang
selama ini dipahami. Bahwa aksi sosial tidaklah sama dengan kerumunan
massa (crowd). Seperti kerumunan massa yang sedang antri di pertamina,
kerumunan massa yang sedang antri menunggu pembagian BLT dari
10
pemerintah, atau mereka yang sedang berada dipasar sentral, kerumunan
massa yang sedang mengejar seorang pencuri di pasar bukanlah
merupakan aksi sosial menurut pengertian Tarrow di atas. Mengingat
rumitya membedakan pengertian mengenai aksi sosial dan aksi massa
yang hampir sama dan luas maknanya, maka dalam tulisan ini perlu
diadakan pembatasan konsep. Dalam analisis Tarrow di atas, kita sudah
dapat menangkap maksud dari apa yang dimaksud dengan aksi sosial
yang penulis maksdukan dalam tulisan ini. Bahwa aksi sosial merupakan
gerakan protes yang terorganisir dan memenuhi sayarat-syarat yang telah
djelaskan di atas. Namun bukakah kerumunan massa (crowd) itu dapat
dikategorikan juga sebagai aksi sosial? Lalu apakah pengertian massa itu?
Kesenjangan konsep ini dapat diselesaikan oleh pengertian yang di
bahas oleh F.Budi Hardiman dalam karyanya yang berjudul: Massa, Teror
dan Trauma; Menggeledah Negativitas Masyarakat Kita. Hardiman
menjelaskan bahwa massa adalah konsentrasi manusia-manusia pada
suatu tempat, dan konsentrasi itu tidak lama bertahan.10 Pengertian ini
dapat dicontohkan seperti kerumunan massa yang sedang antri di
pertamina, kerumunan massa yang sedang antri menunggu pembagian
BLT dari pemerintah, atau mereka yang sedang berada dipasar sentral,
dll. Namun lebih dari itu, Hardiman menekankan ciri yang spesifik dari
suatu kerumunan yang disebut sebagai massa bahwa massa itu tidak
bergerak dalam bingkai-bingkai institusioal, melainkan mengacu pada
aksi-aksi kumpulan manusia yang melampaui batas-batas institusional.
Pengertian melampaui batas-batas institusional mengacu pada pengertian
bahwa sekumpulan manusia menjadi “massa”, jika mereka bertindak
mengabaikan norma-norma sosial yang berlaku dalam situasi sehari-hari.
“Massa” dalam arti ini selalu berkaitan dengan situasi khusus dengan
10 F. Budi Hardiman, Massa, Teror dan Trauma; Menggeledah Negativitas Masyarakat
Kita, (Cet. I, Yogyakarta, Penerbit Lamalera: 2011), hlm., 74
11
keadaan sosial yang abnormal. 11 Melalui pengertian ini, massa tidaklah
sama dengan aksi sosial yang memprotes kebijakan pemerintah, sebab
terikat dalam bingkai hukum dan situasi normal sehari-hari. Namun
begitu banyak orang terprovokasi untuk melakukan tidakan-tindakan
anarkhi, mereka berubah mejadi “massa”.12 Dengan demikian, dapatlah
diketahui perbedaan antara aksi sosial dan aksi massa. Dan dapat pula
kita menjawab pertanyaan bahwa sejak kapan aksi sosial Pembela
Undang-Undang dalam peristiwa 24 September di Buton Utara berubah
mejadi massa?
Teori Tindakan Kolektif
Aksi kekerasa massa tidaklah memadai jika harus dijelaskan melalui
teori prilaku ala Freudian, dan tidak pula memadai jika harus dijelaskan
semata-mata melalui pendirian strukturalis ala Marxis.13. Freud dan
Ortega bersama gurunya Le Bon mengandaikan kekerasan massa sebagi
produk psikis sementara teori-teori Marx menemukan akar-akar
kekerasan dalam ketimpagan-ketimpangan struktural yang tercipta dalam
masyarakat. Diperlukan sebuah teori yang tentunya tidak berada dalam
konfrontasi teoritis yang telah disebutkan, melainkan memadukannya.
Kekerasan massa dapat dikategorikan sebagai tindakan sadar, tidak
terbatas sebagai prilaku. Dalam hal ini, prilaku berkenaan dengan
spontanitas naluriah yang irasional, sementara tindakan menyangkut
kesadaran manusiawi.14
Kebanyakan massa yang mengamuk tidaklah berada dalam keadaan
yang tidak sadar, tidak dalam situasi hipnotis, melaikan dalam keadaan
11 Ibid, hlm., 75 12 Ibid 13 Untuk lebih jelasnya, baca F. Budi Hardiman, Ibid, hlm. 75-78 14 Ibid, hlm. 79
12
sadar dan bertujuan. Hanya saja massa terprovokasi oleh nilai tertentu
yang berhubungan dengan survival-nya. Dengan demikian analisis
terhadap kekerasan massa lebih dapat dijangkau melalui analisis tindakan
kolektif yang tidak parsial memahami sebab-sebab kekerasan massa yang
dihubungkan dengan gejolak mentalitas, atau meluluh disebabkan oleh
analisis ketimpangan struktur sosial.
Menurut Budi Hardiman, analisis teori tindakan kolektif yang
dimaksudkan adalah teori tindakan kolektif Veit Michael Bader. Melalui
teori ini lanjut Hardiman, kita dapat mejelaskan tesis bahwa kekerasan
massa berasal dari tangan manusia, namun dinamika perstiwa ini dapat
melampaui intensi-intensi para pelakunya, bahwa chaos bukanlah ledakan
spontan ressentiment, melainkan dipersiapkan melalui proses-proses
tindakan manusia. Chaos adalah bagian suatu proyek untuk mengubah
suatu tatanan yang tidak adil.15 Melalui teori ini pula, kita dapat
memahami aksi-aksi mahasiswa yang sedang memprotes keras kebijakan
pemerintah sering berakhir dengan kekacauan atau chaos. Demikian pula
aksi kekerasan massa yang terjadi di Buton Utara tidak lahir secara
spontan melainkan dipersiapkan, chaos yang terjadi merupakan proyek
untuk tujuan tertetentu yang hanya diketahui oleh para aktor kekerasan.
Teori tindakan mengkaji massa sebagai sesuatu yang dipersiapkan
oleh manusia. Bader menerangkan unsur-unsur yang mempengaruhi
terbentuknya massa. Menurutnya, sikap kolektif merupakan unsur pertama
dalam pembentukan massa.16 Sikap kolektif yang dimaksud misalnya
karaker agresif preman, sentimen-sentimen agama, rasistis, sentimen dan
polarisasi politk yang menurut Bader seperti dikutip Hardiman
15 Ibid, hlm. 74 16
Pengertian massa yang dimaksud sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya yakni kumpulan manusia yang melakukan tindakan diluar keadaan normal tanpa di batasi oleh batas-batas institusionalisasi.
13
merupakan struktur sosial yang dibatinkan.17 Eric Fromm menyatakan,
bahwa karakter pada manusia merupakan pengganti kebutuhan fisiologis
(dorongan organik; usaha mempertahankan diri) manusia yang kurang
berkembang. Hasrat manusia, seperti cinta, kelembutan hati, kebebasan,
tindakan destruktif, sadis, masokis, dan keinginan lebih lainnya adalah
instrumen untuk memenuhi kebutuhan eksistensialnya, yang berakar dari
kondisi eksistensi manusia tersebut.18 “Penghasut” massa memanfaatkan
kondisi eksistensi individual ini yang dipoles menjadi struktur kognitif
bersama melalui dominasi wacana sosio-politis, melalui penafsiran,
hasutan, oleh budaya, oleh trend, oleh media, hingga sikap-sikap itu
kemudian dibatinkan menjadi ciri khas suatu kelompok. Unsur kedua
pembentukan massa adalah terbentuknya identitas kolektif. Sikap kolektif
yang relatif homogen tanpa disadari membentuk identitas kolektif yang
didefinisikan oleh Bader sebagai “pemisahan dari yang lain”.19
Unsur ketiga pembentukan massa adalah terciptanya kepentingan
Kolektif. Ketegangan-ketegangan akan lebih muda tercipta dalam lapangan
pertarungan kepentingan. Ketika kepentingan kita dan mereka saling
berhadapan, rasa kekitaan suatu kelompok teritegrasi dalam tingkat
resistensi yang tinggi. Bader menjelaskan seperti yang dikutip oleh
Hardiman: “jika para individu mengorientasikan kepentingan-
kepentingan partikular mereka kepada kelompok, sehingga kepentingan-
kepentingan macam itu dapat dibedakan dari kepentingan-kepentingan
kelompok lain terbentuklah kepentingan kolektif.20 Perbedaan identitas dan
kepentingan kolektif ini akan menjadi sangat relevan dengan amukan
massa manakala perbedaan identitas dan kepentingan antara kita dan
17
Op cit, hlm. 91 18
Didik Saputra, Akar-Akar Kekerasan Suporter Sepak Bola (dikutip dalam http://29.wordpress.com, diposting pada tanggal 8 Januari 2011)
19 Op cit, hlm. 91
20 Ibid, hlm. 93
14
mereka terartikulasi secara jelas melalui penafsiran. Dengan demikian
unsur terpenting dari berkumpulnya massa adalah adanya kepemimpinan
dan organisasi. Melalui kepemimpinan dan organisasi, sikap, identitas,
kepentingan ditematisir dan ditafsirkan menjadi sebuah visi tindakan
kolektif. Segala keberatan-keberatan, ketidakpuasan-ketidakpuasan di
artikulasikan, ditematisir dan dikoordinasikan. Menurut Hardiman,
kepemimpinan dan organisasi yang merupakan inti dari gerakan sosial
membentuk suatu jaringan yang rumit. Juga dalam aksi massa yang
tampaknya tak terstruktur, orang dapat mengenali pembagian tugas
tertentu diantara para anggotanya: ada “kristal massa”, yaitu para pemicu
kekerasan massa, penghubung antara kelompok yang satu dengan
kelompok yang lain, informan-informan dan para pelaksana yang hanya
mengikuti perintah dari atas.21
Tahap terakhir yang mengantarkan massa ke ambang tindakan
destruktif adalah mobilisasi. Proses ini menurut Hardiman bukanlah
proses yang sederhana. Peralihan dari massa laten ke massa terbuka tidak
hanya menuntut upaya menyebarkan emosi, agitasi dan provokasi
ditengah-tengah orang banyak. Hal itu juga memerlukan strategi yang
cerdik, kalkulasi, risiko-risiko, pilihan-pilihan sarana dst. Untuk
melancarkan aksi bersama melawan tatanan normatif yang berlaku.22
Peristiwa 24 September di Buton Utara
Sekitar pukul 13.00 WITA, seperti diberitakan oleh beberapa media,
rombongan massa dari kecamatan Bonegunu dan kambowa yang
mengatas namakan Masyarakat Pembela Undang-Undang datang dengan
tiga unit mobil truk, satu unit mobil Dinas Perhubungan yang disandera
21 Ibid, hlm. 95-96 22
Ibid, hlm. 96
15
dalam perjalanan ke Ereke serta puluhan motor.23 Aksi ini merupakan
lanjutan dari aksi sosial yang pernah dilakukan beberapa hari sebelumnya
yang menuntut pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Buton Utara
dari Ereke ke Buranga sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan sesuai
amanah Undang-Undang nomor 17 tahun 2007. Pada aksi massa
sebelumnya Jumat, 23 September 2011, ratusan warga Buranga bahkan
sempat menyandera Dirut RSUD Buton Utara dan membakar mobil Dinas
BKKBN Kabupaten Buton Utara. Aksi tersebut dilakukan dalam bentuk
sweeping yang berlangsung dijalan Ronta.
Kemarahan warga ini memuncak pada Sabtu, 24 September 2011.
Arak-arakan massa dalam tiga truk, satu mobil Dinas Perhubungan dan
ratusan motor menciptakan suasana yang menakutkan dan mengerikan.
Massa seperti halnya rombongan prajurit dalam perang-perang kerajaan
masa lampau yang dilengkapi dengan senjata tajam dan “tameng baja”.
Beberapa pekerja yang sedang membangun gedung di sekitar jalan
menuju kantor DPRD Buton Utara dikagetkan oleh tombak dan kengerian
yang muncul di wajah massa. Tak dapat menahan rasa takut, banyak
pekerja bangunan lari tunggang-langgang mencari tempat persembunyian
yang aman.
Suasana kembali mencekam ketika massa tanpa basa-basi membakar
kantor DPRD Butur. Kepulan asap terlihat di arah Kantor DPRD Buton
Utara. Satu mobil pemadam kebakaran yang datang untuk memadamkan
api juga dibakar oleh massa yang sedang mengamuk. Pihak keamanan,
massa yang pro pemerintah dan Satpol PP tak dapat berbuat apa-apa
karena jumlah mereka yang terbatas di banding dengan massa yang
sedang mengamuk. Massa kemudian bergerak menuju Bumi Sara Ea yang
23
Media Sultra-Sindikasi di http://sindikasi.inilah.com, (diakses pada Minggu, 25 September 2011 pukul 20:27 WIB)
16
merupakan pusat perkantoran pemerintah Kabupaten Buton Utara.
Sasarannya adalah kantor bupati Kabupaten Buton Utara. Disana massa
pembela Undang-Undang sebelumnya mendapatkan perlawanan dari
massa yang pro pemerintah, namun aksi pembakaran tidak dapat
dihentikan karena jumlah yang sedikit.
Kepulan asap menghiasi Kantor Bupati Buton Utara saat dilalap oleh
api yang dipicu oleh massa. Warga Ereke kemudian diresahkan oleh isu
pembakaran pasar sentral dan rumah jabatan bupati oleh massa pembela
Undang-Undang. Pasca pembakaran kantor bupati, massa pembela
Undang-Undang mendapat perlawanan yang sengit dari massa pro
pemerintah. Dua massa yang saling berhadap-hadapan itu saling serang
dengan busur, tombak dan batu akibatnya seorang warga terluka akibat
terkena busur. Namun akhirnya dapat dibubarkan oleh aparat kepolisian.
Aksi kekerasan dan saling serang ini mengandaikan dua
kepentingan kolektif berbeda. Antara kita dan mereka bertemu dalam
lapangan sosial yang banal. Massa pembela Undang-Undang
menyebarkan teror yang telah dipersiapkan dengan melancarkan strategi
chaos untuk menentang sistem yang berlaku, sementara massa pro
pemerintah teritegrasi dalam upaya perwujudan kepentingan yang
berbeda dan terlebih lagi adalah dorongan naluri bertahan ketika
mendapatkan serangan dari kelompok identitas berbeda. Bagaimana pun
juga, massa pro pemerintah bukanlah kelompok yang secara spontan
terbentuk tanpa memenuhi unsur-unsur pembentukan massa sepeti
analisis teori tindakan kolektif yakni adanya sikap kolektif, identitas
kolektif, kepentingan kolektif, organisasi dan kepemimpinan serta
mobilisasi massa.
Seperti kata Bader terdapat sikap yang dibatinkan dalam benak
kepala massa. Massa yang kelihatan spontan sekalipun sebenarnya
17
terpola oleh proses sosial-politik, keakraban, identitas, dll. yang telah lama
ada dan terbentuk diluar situasi formal dan bahkan tidak disadari.
Polarisasi dukungan dalam proses demokrasi misalnya, memberi peluang
untuk menciptakan identitas baru, kepentingan baru dan keakraban-
keakraban baru. Pola yang terbatinkan ini menjadi kategori-kategori yang
berpeluang menyulut gerakan massa yang terlihat spontan sekalipun.
Intinya tak ada spontanitas aksi massa, semuanya dipersiapkan oleh
proses-proses dan relasi-relasi sosial yang rumit. Massa juga tidak lepas
dari kepemimpinan dan mobilisasi. Dalam massa yang kelihatan spontan,
kepemimpinan terbentuk dari pengakuan sosial terhadap kapasitas
seseorang yang juga terbatinkan melalui proses sosial yang berlangsung
dalam ruang dan waktu, juga dapat terbentuk dari organisasi-organisasi
non formal seperti komunitas preman dan kelompok-kelompok pemuda.
Namun dalam massa yang terorganisir, massa bertindak dalam
pembagian tugas, strategi-strategi, kalkulasi-kalkulasi, ketundukan dan
risiko-risiko yang diperhitungkan sebelumnya secara cerdik.
Monster berkepala banyak itu bergerak tanpa kendali moral dan
norma-norma bukan karena mereka tidak memiliki nurani sebagai
manusia. Pikiran dan tindakan massa berada dalam prinsip kepatuhan
yang ditafsirkan dan dibatinkan. Seperti studi yang pernah dilakukan oleh
Hannah Arendt mengenai Adolf Eichmann dalam karyanya yang
berjudul: Eichmann in Jerusalem. Eichmann adalah kaki tangan Hitler yang
bertanggung jawab terhadap pemusnahan orang Yahudi. Pada dasarnya,
Eichmann adalah seorang warga negara dan birokrat yang baik, namun
dalam menjalankan kepatuhannya terhadap rezim Nazi ia melakukan
tindakan-tindakan di luar batas-batas moralitas dan norma-norma
kemanusiaan. Untuk memecahkan persoalan ini, kita dapat mempelajari
percobaan Stanley Milgram yakni the Milgram experiment. Dalam
18
percobaan itu Milgram menggunakan tiga orang untuk berperan dalam
instrumen penelitian. Seorang sebagai pemimpin eksperimen, seorang
orang berperan sebagai guru (posisi ini diganti-ganti) dan satu orang
berperan sebagai siswa.24
Peserta dari percobaan ini dicari melalui sebuah iklan di koran lokal
yang mengumumkan bahwa dibutuhkan orang untuk berpartisipasi
dalam sebuah studi tentang memori. Sebagai kompensasi, setiap peserta
menerima uang sebesar $ 4.50. Iklan tersebut juga menyebutkan profesi-
profesi apa saja yang diharapkan untuk berpartisipasi. Percobaan pun
berjalan setelah didapatkan total 40 partisipan. Setiap partisipan
mengambil undian yang tanpa mereka ketahui selalu bertuliskan "guru"
dan partisipan lainnya, yang sebenarnya adalah aktor, bertindak sebagai
"murid". Kemudian "guru" dan "murid" masuk ke ruangan yang berbeda.
Tugas dari guru adalah membacakan rangkaian soal dan murid
menjawabnya dengan menekan tombol pada mesin yang disediakan.
Apabila jawaban yang diberikan salah maka guru harus memberikan
tegangan listrik kepada murid. Tegangan listrik tersebut bertahap mulai
dari 15 volt hingga 450 volt dan diberikan label mulai dari "tegangan
rendah", "tegangan sedang" hingga "bahaya: tegangan listrik fatal"
sedangkan dua volt tertinggi bertuliskan "XXX". Ketika mencapai level 300
volt, murid akan mengetuk-ngetuk dinding memohon agar percobaan
dihentikan. Diatas 300 volt, murid akan diam dan menolak untuk
menjawab pertanyaan yang lalu oleh penguji akan dianggap sebagai
jawaban salah sehingga tegangang listrik harus diberikan. Sampai tingkat
tegangan listrik mana partisipan berhenti menjadi ukuran dari
kepatuhannya terhadap otoritas. Dari 40 orang yang menjadi peserta
24
F. Budi Hardiman, Op cit, hlm. 137
19
percobaan ini sebanyak 26 orang memberikan tegangan tingkat tertinggi
sementara 14 orang berhenti sebelum mencapai tingkat paling tinggi.25
Percobaan Milgram ini memberi penjelasan adanya kepatuhan
terhadap otoritas atau sistim yang sedang dijalankan. Demi menjalankan
prosedur eksperimen sang Professor, para peserta rela memberikan
kejutan listrik pada peserta lainnya (yang bertindak sebagai murid).
Demikianlah juga ketika Adolf Eichmann disidang pasca perang dunia II
karena kejahatannya sebagai seorang Nazi yang banyak membunuh orang
Yahudi, dalam kesaksiannya ia mengatakan: “saya hanya menjalankan
perintah atasan saya”.
Mobilisasi dalam aksi kekerasan massa itu dipermudah oleh adanya
ketundukan atau adanya otoritas yang menguasai alam kognitif massa.
Ketundukan seperti diperlihatkan oleh percobaan Milgram di atas terjadi
karena misanya adanya otoritas keilmuan Professor Stanley Milgram yang
terjewantahkan dalam prosedur penelitian, dan boleh jadi karena
ketundukan terhadap uang sebesar $ 4.50 yang dibayarkan pada peserta
eksperimen. Dalam aksi kekerasan, ketundukan karena otoritas uang
dapat saja terjadi yang membuat massa dapat diperintah atau disetir
seperti mesin. Tubuh memimesis kerja-kerja mesin.
Berdasarkan penjelasan di atas, menurut hemat penulis, tragedi
kekerasan massa pada 24 September di Buton Utara terjadi tidak hanya
disebabkan oleh adanya penafsiran Undang-Undang Nomor 17 tahun
2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara. Dalam hal ini yang
dipersoalkan adalah masalah ibu kota. Sebagaimana analisa teori tindakan
kolektif, ada beberapa faktor potensial yang mendorong atau mentenagai
penafisran UU itu menjadi aksi kekerasan massa diataranya:
25
http://id.wikipedia.org/wiki/Percobaan_Milgram
20
Pertama, adanya sikap kolektif masyarakat Buton Utara yang
cenderung agresif dalam menanggapi problem-problem kehidupan. Hal
ini dapat dilihat setidaknya dalam kacamata sosial-budaya. Ada struktur
budaya kekerasan yang mewariskan dari masa lalu seperti ilmu kebal,
silat, keris pusaka dan beberapa mantra yang diyakini dapat digunakan
untuk berkelahi. Dalam hal ini, antara massa pro pemerintah dan
penyelamat undang-undang sama-sama mewarisi sikap agresif yang
terbatinkan itu.
Kedua, adanya identitas kolektif yang terbentuk berdasarkan proses
sosial-politik yang berlangsung di Buton Utara. Identitas sosial-budaya
ada dua macam: 1) identitas Ereke (Kecamatan Kulisusu) sebagai bekas
Barata Kulisusu yang memengaruhi struktur berpikir masyarakat untuk
cenderung mempertahankan kondisi yang telah ada (sebagai ibukota
Kabupaten Buton Utara), sementara Buranga mempertahankan identitas
mereka sebagai wilayah yang direstui Undang-Undang sebagai ibukota
Kabupaten Buton Utara. 2) identitas yang terbentuk kerena polarisasi
politik antara massa pendukung kandidat dalam proses demokrasi.
Identitas ini merupakan identitas baru yang terbentuk namun sangat
berpengaruh terhadap berlangsungnya proses politik di Buton Utara.
Identitas kedaerahan antara Ereke dan Buranga dapat saja terlebur oleh
adanya identitas baru ini. Individu sebagai agen melakukan tindakan
untuk keluar dari struktur. Artinya bahwa orang Ereke dapat saja terlibat
dalam Masyarakat Pembela Undang-Undang juga sebaliknya orang
Buranga dapat saja berada dalam massa yang pro pemerintah.
Ketiga, adanya kepentingan kolektif. Kepentingan ini diturunkan
dari perbedaan identitas. Sebab identitas itu memiliki pertalian dengan
kepentingan kelompok. Kepentingan kolektif juga dapat dilihat dari dua
hal dan dua sisi yang berhadap-hadapan berdasarkan identitas kolektif
21
yang disebutkan diatas. 1) kepentingan yang muncul karena adanya
identitas kedaerahan Ereke dan Buranga: a) Bagi Buranga mewakili
adanya ketimpangan-ketimpangan yang dirasakan oleh masyarakat
akibat proses pemerintahan yang sedang berlangsung termasuk
ketimpangan pembangunan yang belum merata, pelayanan publik yang
tidak efisien, dan keberatan terhadap adanya keberpihakan UU pada
mereka yang justru tidak direalisasikan oleh pemerintah daerah. dalam
teori strukturalisme-fungsional, Buranga merasa berada dalam struktur
yang dirugikan. Dalam hal ini misalnya masyarakat Buranga harus
membayar pajak layaknya penduduk yang berada di Ibukota Kabupaten.
b) Bagi Ereke yakni: adanya kepentingan akan pembangunan dan
pelayanan yang sudah terlanjur dinikmati, serta keadaan wilayah yang
cukup memadai membuat struktur kognitif mereka cenderung
membenarkan tidakan pemerintah yang menempatkan pusat
pemerintahan dan bahkan ibukota Kabupaten Buton Utara berada di
Ereke. Juga adanya ingatan sosial dimana Ereke adalah wilayah bekas
Barata Kulisusu yang dari dulu merupakan pusat pemerintahan. 2)
kepentingan yang muncul akibat adanya identitas dukungan politik
yakni: Bagi pendukung kandidat yang menang, akan cenderung
mempertahankan dan membela tindakan pemerintah, sedangkan
pendukung kandidat yang kalah akan cenderung menjadi kelompok
oposisi yang selalu berusaha mencari titik lemah pemeritah yang sedang
berkuasa. Pembangunan pusat pemerintahan di luar amanh UU
merupakan celah yang dapat dimanfaatkan pihak oposisi untuk
melancarkan serangan terhadap pemerintah. Dengan demikian dalam
sudut pandang ini, dapat dimaknai bahwa massa pembela UU melakukan
aksi pembakaran gedung di Ereke (chaos) merupakan salah satu strategi
oposisi untuk melawan kebijakan pemerintah dan massa pro pemerintah
juga segera terbentuk untuk mengadakan upaya perlawanan. Dari
22
penjelasan ini, jelaslah bahwa tak ada massa yang terbentuk secara
spontan, melainkan terbentuk dari akar-akar sosial-politik yang telah
terstruktur dan telah mengakar tanpa disadari (terbatinkan).
Keempat, adanya kepemimpinan dan organisasi. Kemarahan, akar-
akar identitas dan kepentingan yang tercipta dalam masyarakat akan
menjadi jelas arahnya bila ada aktor sosial yang mampu
mengartikulasikan keberatan-kebaratan itu dalam sebuah “visi” dan
strategi-strategi tindakan kolektif yang mungkin untuk dilakukan.
Disinilah fungsi kepemimpinan dan organisasi. Baik massa pro
pemerintah maupun massa pembela UU menjadi mungkin untuk
melakukan tindakan kolektif karena adanya faktor kepemimpinan dan
organisasi. Walau pun tak terbentuk secara formal, selalau ada “kristal
massa” yang betindak sebagai pemicu, pusat komando, dan lebih
tepatnya kita sebut pemimpin massa.
Kelima, adanya mobilisasi massa yang merupakan tahap terakhir
yang mengantarkan massa pada objek kemarahannya. Mobilisasi ini dapat
terjadi karena adanya kepatuhan kelompok massa terhadap visi
kelompoknya. Kepatuhan itu dapat saja tercipta karena setiap individu
dalam massa terikat oleh identitas dan kepentingan yang sama, dan
adanya otoritas kepemimpinan massa. Individu dalam massa dapat pula
mengalami kepatuhan karena adanya otoritas yang muncul melalui
mekanisme pembayaran sejumlah uang yang dapat diterima sebagai
imbalan.[]