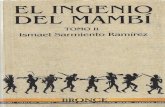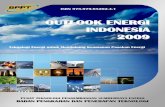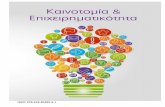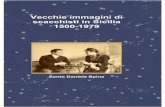EL INGENIO DEL MAMBÍ. Tomo 1, Santiago de Cuba, Ed. Oriente, 2008, 352 p. ISBN: 978-959-11-0620-9
NOMOR ISBN : 978-979-587-897-1
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of NOMOR ISBN : 978-979-587-897-1
PROSIDING
SEMINAR NASIONAL
KESEHATAN MASYARAKAT
SRIWIJAYA
© FKM UNSRI 2020
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Copyright @ 2020 by FKM Universitas Sriwijaya
NOMOR ISBN : 978-979-587-897-1
EDITOR :
Yeni, S.K.M., M.KM.
Indah Purnama Sari, S.KM.M.K.M
Inoy Trisnaini, SKM., M.KL
Amrina Rosyada, S.K.M., M.PH
Prosiding ini dipublikasikan oleh:
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya
Kampus FKM Unsri Indralaya, Jl. Raya Palembang-Prabumulih KM.32
Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 30662
Hotline : +62711580068
Fax : +62711580089
Penerbit : Unsri Press
Universitas Sriwijaya Kampus Palembang
Jln. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang 30139
Tlp. 0711360969/085366741970
Email : [email protected]/[email protected]
SUSUNAN PANITIA SEMINAR
PROCIDING SEMINAR NASIONAL
KESEHATAN MASYARAKAT SRIWIJAYA
Palembang, 13-14 Oktober 2020
SUSUNAN PANITIA
Pelindung : Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE
Penasehat Iwan Stia Budi, S.K.M., M.Kes
Penanggung Jawab : Dr. Misnaniarti, S.KM, M.KM
Pengarah : 1. Asmaripa Ainy, S.Si., M.Kes
2. Dr. Yuanita Windusari, S.Si., M.Si.
3. Dr. Nur Alam Fajar, S.Sos., M.Kes
Ketua : Feranita Utama, S.K.M., M.Kes
Wakil Ketua : Yustini Ardillah, S.K.M., M.P.H
Seksi Kesekterariatan dan
Registrasi
: 1. Dwi Septiawati, S.K.M., M.K.M (Koordinator)
2. Drs. H. Fathul Hartama, M.Si
3. Dwi Siti Aisyah, S.Sos
4. Abileo, A.MAK
Seksi Humas : 1. Widya Lionita, S.K.M., M.P.H (Koordinator)
2. Desheila Andarini, S.K.M., M.Sc
3. Devi Laila. S.Pd
Seksi Acara : 1. Dini Arista Putri, S.Si., M.P.H (Koordinator)
2. Rahmatillah Razak, S.K.M., M.Epid
3. Ditia Fitria Arinda, S. Gz., M.P.H
Seksi Ilmiah & Publikasi : 1. Yeni, S.K.M., M.KM. (Koordinator)
2. Amrina Rosyada, S.K.M., M.PH
3. Indah Purnama Sari, S.K.M., M.K.M
4. Inoy Trisnaini, S.KM, M.K.L
5. Ima Fransiska, S. Sos
Seksi Acara Bagian Panel : 1. Fenny Etrawati, S.KM., M.KM. (Koordinator)
2. Dian Safriantini, S.K.M., M.P.H
Seksi Acara Bagian Perlombaan : 1. Anggun Budiastuti, S.K.M., M.Epid (Koordinator)
2. Indah Yuliana, S.Si., M.Si.
Seksi Dokumentasi dan Publikasi : 1. Mona Lestari, S.K.M., M.K.K.K
2. Desri Maulina Sari, S.Gz., M.Epid
3. Dedi Kurniadi, S.Pd
4. Amin Ibrahim, A.Md
Akomodasi dan Perlengkapan
1. Hamin, S.E. (Koordinator)
2. Rachman Kamaludin
3. Sunyoto, S.E
4. Ismail
Seksi Konsumsi : 1. Kurnila Yulia Hirti, S.E. (Koordinator)
2. Muslimaini, S.E
3. Siti Amaliah, S.E
Dekan,
Dr. Misnaniarti, S.KM., M.KM
NIP. 197606092002122001
i Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT, sang Pengatur Alam Semesta, yang telah melimpahkan
kasih-Nya sehingga Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya dapat
menyelenggarakan Seminar Nasional Fakultas Kesehatan Masyarakat 2020 dengan
tema “Peluang dan Tantangan Epidemiologi Dalam Ketahanan dan Kesehatan Global
di Era Pandemi Covid-19”. Seminar ini diselenggarakan pada tanggal 13-14 Oktober
2020.
Seminar ini bertujuan sebagai wadah bertukar pikiran antara para akademisi, praktisi,
peneliti, dan pemangku kebijakan tentang bagaimana peluang dan tantangan epidemiologi
dalam ketahanan dan kesehatan global di era pandemi covid-19 sehingga diharapkan dapat
meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peluang dan tantangan yang akan dihadapi
terhadap permasalahan kesehatan dalam masa pandemic covid-19. Selain itu, kegiatan ini
juga menjadi penyalur bakat dan kreativitas mahasiswa melalui lomba poster, karya ilmiah,
dan video.
Atas nama panitia penyelenggara, saya dengan senang hati menyambut anda semua
di seminar nasional ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber
yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu di seminar ini. Besar harapan kami
untuk tetap terus menjalin silahturahmi dengan para akademisi, praktisi, peneliti, dan
pemangku kebijakan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Akhir kata, semoga kegiatan
ini dapat terus berlanjut dan dapat bermanfaat untuk kita semua.
Palembang, 13 Oktober 2020
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Sriwijaya
Dr. Misnaniarti, S.KM., M.KM
NIP. 197606092002122001
ii Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam, karena dengan rahmat dan
karuniaNyalah kegiatan Seminar Nasional dan Calls for Paper dengan tema: “Peluang dan
Tantangan Epidemiologi dalam Ketahanan dan Kesehatan Global di Era Pandemi Covid
19” dapat terselenggara dengan baik dan prodising ini dapat diterbitkan. Covid 19 telah
banyak memberikan dampak pada Negara kita, bukan hanya sektor kesehatan tetapi
banyak sektor lainnya juga terdampak Pandemi Covid 19 ini. Tema ini dipilih sebagai
salah satu sumbangsih dari dunia pendidikan menyikapi kondisi yang ada pada saat ini.
Beberapa topik dalam prosiding ini meliputi Administrasi Kebijakan Kesehatan,
Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan, Gizi
Masyarakat dan Ilmu Gizi, Biostatistik, Epidemiologi dan Covid 19. Prosiding ini
merupakan salah satu alternatif bagi akademisi maupun praktisi melakukan diseminasi
hasil penelitian dan pemikiran mereka terhadap permasalahan kesehatan yang ada pada
saat ini, sehingga hasil penelitian dan pemikiran dapat diketahui dan bermanfaat untuk
banyak pihak.
Kegiatan seminar nasional ini telah diselenggarakan pada tanggal 13 dan 14 Oktober
2020. Peserta kegiatan seminar dan pemakalah tidak hanya berasal dari beberapa
perguruan tinggi di Indonesia tetapi juga diikuti oleh beberapa institusi seperti
Balitbangkes baik pusat maupun daerah dan beberapa puskesmas di Indonesia.
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Universitas Sriwijaya,
terutama Pimpinan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Peserta Seminar, Pemakalah, dan
segenap Panitia yang telah menyukseskan acara ini. Semoga Allah swt membalas dengan
kebaikan semua usaha yang telah kita lakukan. Wassalamu’alaikum wr.wb.
Indralaya, 23 Oktober 2020
Ketua Panitia
Feranita Utama, S.KM., M.Kes.
NIP. 198808092018032002
iii Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020
SUSUNAN ACARA SEMINAR NASIONAL
PELUANG DAN TANTANGAN EPIDEMIOLOGI DALAM
KETAHANAN DAN KESEHATAN GLOBAL DIERA PANDEMI
COVID -19
FAKULTAS KESEHATAN
MASYARAKAT
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Waktu (Jam) Judul Kegiatan Penyelenggara
Hari 1 ( 13 Oktober 2020)
08.00-08.30 Registrasi dan administrasi peserta seminar
Panitia Registrasi melalui online
08.30-09.00 Pembukaan Mc: Ridho fathoni
Menyanyikan lagu Indonesia raya panitia
Kata sambutan ketua panitia Feranita Utama,S.KM.,M.Kes
Kata Sambutan Dekan Fakultas Kesehatan
Masyarakat
Dr. Misnaniarti, S.KM, M.KM
Pembacaan Doa Fachri Reza
09.00-09.05 Penyampaian Materi dan Diskusi Moderator: Rico Januar Sitorus,S.KM.,M.Kes
09.05-09.50
Situasi kesehatan Global dan
Defriman Djafri,S.KM.,M.KM.,Ph.D pencegahan peningkatan
masalah kesehatan
masyarakat
09.50-10.35
Strategi perbagikan kesehatan
Dr. Yodi Mahendradhata,M.Sc.,Ph.D Global di Era Pandemi
COVID-19
10.35-10.40
Ice breaking
Panitia
10.40-11.25
Tantangan dan Peluang
Najmah Usman,S.KM.,M.PH.,Ph.D Epidemiologi dalam
menghadapai isu kesehatan
Global
iv Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020
11.25-12.00 Diskusi Moderator: : Rico Januar
Sitorus,S.KM.,M.Kes
12.00-12.05 Penutup Mc: Ridho fathoni
13.00- 16.00 Pengumuman lomba
Lomba poster
Lomba essay
Lomba video
Lomba pidato bahasa inggris
Panitia
Hari II (14 Oktober 2020)
08.00-08.30 Registrasi dan administrasi peserta
seminar
Panitia Registrasi melalui online
08.30-11.55 Parallel session
Moderator
Dr.Rostika Flora,S.Kep.,M.Kes
Moderator
Dr.rer.med.Hamzah Hasyim,S.KM.,M.KM
Moderator
Dr.Nur Alam Fajar,S.Sos.,M.Kes
Moderator
Dr.Novrikasari,S.KM.,M.Kes
Moderator
dr. Rizma Adlia Syakurah,MARS
Moderator Dr. Yuanita Windusari,S.Si.,M.Si
ROOM 1
Gizi dan Epidemiologi
ROOM 2
Kesehatan Lingkungan
ROOM 3
(Administrasi kebijakan kesehatan/
Promosi Kesehatan)
ROOM 4
(Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
ROOM 5
(Covid -19)
ROOM 6 (Gabungan)
11.55-12.00 Penutup Panitia
v Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020
KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR SUSUNAN KEGIATAN SEMINAR NASIONAL
DAFTAR ISI
i
ii
iii
v
1. Pengaruh Pemberian MP-Asi Dini dengan Kejadian Stunting Pada Balita 24-59 Bulan di
Indonesia (Analisis Data Ifls 5)
Meike Rahyuni, Amrina Rosyada
2. Toluene Exposure Management for Printing Machine Operators in Offset Printing
Companies
Widya Haris Saraswati, Mona Lestari, Novrikasari, Dini Arista Putri, Anita
Camelia
3. Perbandingan Sanitasi Sekolah Dasar Berdasarkan Akreditasi Sekolah: Studi Kualitatif
Russy Rakhmalia, Yustini Ardillah
4. Penilaian Risiko Pajanan Pestisida dengan Pendekatan Hira (Hazard Identification And
Risk Assesment) Pada Petani Pengguna Pestisida
Rina Purwandari, Sidiq Purwoko, Ina Kusrini
5. Prediksi Berat Lahir Rendah Melalui Tren Konsentrasi Nitrogen Dioksida di Udara
Ambien Kota Palembang
Dwi Septiawati, Imelda G. Purba, Ani Nidia Listianti
6. Gejala Klinis Penyakit Covid-19 Pada Bayi dan Anak : Studi Literatur
Komalasari, Ade Tyas Mayasari,
Elsa Fitri Ana
7. Gambaran Penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pada Stakeholder di Wilayah
Kerja Puskesmas Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Tahun 2019
Mayumi Nitami, Decy Situngkir
8. Istribusi Balita Third Hand Smoke di Kota Palembang
Amrina Rosyada, Dini Arista Putri, Nurmalia Ermi
9. Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku 3M (Menggunakan Masker, Menjaga Jarak, dan
Mencuci Tangan Dengan Sabun) Masyarakat Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19
Heny Lestary, Cahyorini, Khadijah Azhar, Sugiharti
10. Evaluasi Pemeriksaan dan Pengujian K3 pressure vessel oleh Ahli K3 Pesawat Uap dan
Bejana Tekanan Berdasarkan Permenaker No. 37 Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung pada tahun 2018 dan 2019
Maududi Farabi, Mila Tejamaya
11. Peran Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Pencegahan Kematian Akibat Covid-19
di Indonesia
Siti Masitoh, Teti Tejayanti, Sugiharti, Heny Lestary, Helena Ullyartha
Pangaribuan
12. Keselamatan dan Kesehatan Kerjapada Proses Pemotongan Batu Padas di Workshop
Sari Yasa Kota Denpasar
I Gusti Agung Haryawan, Komang Angga Prihastini, Ni Putu Diana Swandewi
13. Evaluasi Kinerja Kader Posyandu Bayi dan Balita di Wilayah Kerja Puskesmas
Banguntapan II Bantul
Rosikhah Al-Maris, Pamulatsih Dwi Oktavianti
14. Identifikasi Kejadian Hipertensi dan Obesitas Sentral Pada Pra Lansia
Yeni, Fenny Etrawati,
Feranita Utama
15. Implementasi Model Arima (Autoregressive Integrated Moving Average) Guna
Peramalan Kasus Demam Berdarah Dengue di Kota Semarang
Roro Kushartanti, Maulina Latifah
16. Studi Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Rumah Sakit Umum
Daerah Prambanan (Rumah Sakit Tipe C) Kabupaten Sleman Daerah Istimewa
Yogyakarta
Haidar Prawira, Ariyanto Nugroho, Theresia Puspitawati
17. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di Praktik Mandiri Bidan pada Pertolongan
1
11
24
34
46
55
61
68
74
87
105
115
119
135
142
147
155
vi Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020
Persalinan
Sugiharti, Heny Lestary, Eva Laelasari
18. Kontribusi Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Masyarakat Terhadap Masalah Penyakit
Infeksi Pernapasan
Ika Dharmayanti, Dwi Hapsari Tjandrarini,Olwin Nainggolan, Zahra
19. Prevalensi Penyakit Jantung Pada Usia Produktif Menjadi Ancaman Terhadap Kualitas
Bonus Demografi di Indonesia: Tinjauan Literatur
Basuki Rachmat, Khadijah Azhar
20. Studi Kohort : Analisis Ketahanan Hidup Pasien Hemodialisis Dengan Komorbid
Hipertensi Di Rumah Sakit Abdoel Moeleok, Lampung
Nurhalina Sari, Nova Muhani, Dias Dumaika, Aprizal Hendardi
21. Pemanfaatan Hasil Studi Kohor Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (FRPTM) di
Kota Bogor 2011—2019
Sulistyowati Tuminah, Woro Riyadina, Sudikno, Dewi Kristanti
22. Peran Gejala Depresi Terhadap Kejadian Penyakit Tidak Menular pada Populasi Umum
Tahun 2007-2014
Rofingatul Mubasyiroh, Tri Wuriastuti
23. Perilaku Masyarakat Tentang Pencegahan Demam Berdarah Dengue di Daerah Endemis
dan Non Endemis Kota Pekanbaru
Tyagita Widya Sari, Martha Saptariza Yuliea, Novita Meqimiana Siregar,
Raudhatul Muttaqin
24. Determinan Pemilihan Alat Kontrasepsi di Puskesmas Makrayu Palembang
Farina Eka Agustine, Dian Safriantini
25. Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) Pada Balita Gizi Kurang Ditinjau
Dari Teori Perilaku Terencana (TPB)
Ersa Yolanda, Fatmalina Febry
26. Profil Tahapan Anemia Defisiensi Besi Pada Anak Sekolah Dasar Di Daerah Pedesaan:
Studi Cross Sectional Di Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas
Rostika Flora, Mohammad Zulkarnain, Nur Alam Fajar, Achmad Fickry Faisa ,
Indah Yuliana, Nurlaili, Ikhsan, Samwilson Slamet, Risnawati Tanjung, Aguscik
27. Analisis Faktor Risiko Kejadian Katarak di Indonesia
Bima Andika Persada, Feranita Utama
28. Analisis Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Kebakaran di Kelurahan Tuan Kentang
Kecamatan Jakabaring Palembang 2019
Ade Pratama, Novrikasari
29. Deteksi Resiko Anemia dan Pendidikan Gizi Prakonsepsi Pada Calon Pengantin Wanita
di Kabupaten Oki Sumatera Selatan
Ditia Fitri Arinda, Rostika Flora, Widya Lionita
30. Korelasi Frekuensi Senam Hamil Dengan Lama Persalinan Kala II Di Rumah Sakit
Umum YK Madira Palembang Tahun 2020
Erma Puspita Sari, Rini Gustina Sari
31. Perubahan Kesadaran Kesehatan Akibat Pandemik Covid-19 Pada Mahasiswa di
Sumatera Selatan
Windi Indah Fajar Ningsih, Fatmalina Febry,
Indah Purnama Sari, Ditia Fitri
Arinda
32. Manajemen Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil Dimasa Pandemi Covid-19 : Tinjauan
Literatur Terkini
Ade Tyas Mayasari, Elsa Fitri Ana, Komalasari, Dessy Nur Safitri
33. Determinan Keluhan Mata pada Pekerja di Depot Pasir Kota Palembang
Dini Arista Putri, Amrina Rosyada,
Desri Maulina Sari
164
172
185
193
210
222
229
238
245
251
261
271
279
287
299
312
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 1
PENGARUH PEMBERIAN MP-ASI DINI DENGAN KEJADIAN STUNTING
PADA BALITA 24-59 BULAN DI INDONESIA
(ANALISIS DATA IFLS 5)
Meike Rahyuni,
1 Amrina Rosyada,
2*
1Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya
2Bagian Epidemiologi dan Biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya
1,2Jl. Palembang Prabumulih KM.32, Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan
*Corresponding email: [email protected]
EFFECT OF COMPLEMENTARY FEEDING ON EARLY BREASTFEEDING WITH
INCIDENCE OF STUNTING IN INFANTS 24-59 MONTHS IN INDONESIA (DATA
ANALYSIS OF IFLS 5)
ABSTRACT
Stunting is a condition that describes a history of malnutrition accompanied by stunted growth due to long-
term malnutrition. The impact of stunting, namely low endurance, reduced intelligence. This study aims to
see the effect of early complementary breastfeeding with the incidence of stunting in infants 24-59 months in
Indonesia. This study used a cross sectional study design. This study used secondary data, namely IFLS in
2014. The sample of this study was 1006 toddlers who were the last children in the 2014 IFLS survey. The
sampling method used was multistage random sampling. Data analysis using a complex sample. Bivariate
analysis with chi-square test and multivariate analysis with multiple logistic regression. The prevalence of
stunting among infants 24-59 months in Indonesia is 43.8%. The results of bivariate analysis showed that
there was a significant relationship between early complementary breastfeeding and the incidence of stunting
(p-value = <0.0001). The results of multivariate analysis showed that the effect of early complementary
breastfeeding showed that the adjusted PR value was 1.873 (95% CI 1.529-2.293) controlled by variables of
infant birth weight, maternal height and immunization status. Early complementary feeding has a major
effect on the incidence of stunting in infants 24-59 months in Indonesia after being controlled by variables of
birth weight, maternal height and immunization status. Suggestions for cross-sectoral collaboration to deal
with problems with nutritional status, conduct early detection activities by measuring children's height
routinely, which can be carried out in posyandu activities, need support for mothers to keep trying to provide
exclusivity until the baby is 6 months old.
Keywords: Toddlers, early complementary breastfeeding, stunting
ABSTRAK
Stunting merupakan keadaan yang menggambarkan riwayat kekurangan gizi disertai dengan terhambatnya
pertumbuhan karena malnutrisi yang terjadi dalam jangka waktu lama. Dampak dari stunting yaitu
rendahnya daya tahan tubuh, menurunkan kecerdasan.Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh
pemberian MP-ASI dini dengan kejadian stunting pada balita 24-59 bulan di Indonesia. Penelitian ini
menggunakan desain penelitian cross sectional. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu IFLS tahun
2014. Sampel penelitian ini adalah balita yang merupakan anak terakhir dalam survei IFLS tahun 2014
sebanyak 1006 balita. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan multistage random sampling.
Analisis data menggunakan complex sampel. Analisis bivariat dengan uji chi-square dan analisis multivariat
dengan regresi logistik berganda. Prevalensi kejadian stunting pada balita 24-59 bulan di Indonesia sebesar
43,8%. Hasil analisis bivariat diperoleh terdapat hubungan yang bermakna antara pemberian MP-ASI dini
dengan kejadian stunting (p-value = <0,0001). Hasil analisis multivariat menunjukkan besar pengaruh
pemberian MP-ASI dini yang terlihat nilai adjusted PR yaitu sebesar 1,873 (95% CI 1,529-2,293) dikontrol
dengan variabel berat badan lahir bayi, tinggi badan ibu dan status imunisasi. Pemberian MP-ASI dini
memiliki pengaruh besar terhadap kejadian stunting pada balita 24-59 bulan di Indonesia setelah dikontrol
dengan variabel berat badan bayi lahir, tinggi badan ibu dan status imunisasi. Saran penelitian adanya kerja
sama lintas sector untuk menangani permasalahan status gizi, melakukan kegiatan deteksi dini dengan cara
mengukur tinggi badan anak secara rutin yang dapat dilakukan pada kegiatan posyandu perlu adanya
dukungan kepada ibu agar tetap berusaha memberikan esklusif hingga bayi berusia 6 bulan.
Kata Kunci : Balita, MP-ASI dini, Stunting
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 2
PENDAHULUAN
Di Negara berkembang seperti Indonesia angka kematian bayi dan anak masih tinggi terjadi.
Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satu nya status gizi kurang yang terjadi pada
anak. Status gizi buruk pada bayi dan anak dapat menimbulkan terhambatnya pertumbuhan fisik
mental maupun kemampuan berfikir pada anak sehingga berdampak pada menurunnya
produktivitas kerja dan kualitas sumber daya manusia. Keadaan gizi kurang merupakan keadaan
gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari dan
terjadi dalam waktu lama.(1)
Status gizi kurang merupakan proses kurang nya supan makanan
dimana kebutuhan zat gizi normal tidak terpenuhi. Kekurangan gizi kronis berdampak pada
pertumbahan anak yang tidak optimal, apabila hal ini berlangsung lama dapat mengakibatkan
kejadian stunting pada anak.(2)
Stunting merupakan suatu keadaan yang menggambarkan riwayat kekurangan gizi yang
disertai dengan terhambatnya pertumbuhan karena malnutrisi yang terjadi dalam jangka waktu
yang lama. Meskipun terjadinya kurang gizi pada saat masa kehamilan dan pada awal kelahiran
bayi, kejadian stunting baru bisa dilihat pada saat umur anak tersebut 2 tahun.(3)
Berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2013 Prevalensi stunting di Indonesia cukup tinggi
yaitu 37,2% yang terdiri dari 18% anak sangat pendek dan 19,2% anak pendek. Prevalensi stunting
di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan Negara lain di Asia Tenggara, seperti di Negara
Myanmar dengan prevalensi stunting sebesar 35%, Negara Vietnam prevalensi stunting sebesar
23% dan di Negara Thailand sebesar 16% kondisi stunting di di Indonesia menduduki peringkat ke
lima dunia.(4)
Kekurangan gizi dapat mengakibatkan gagalnya pertumbuhan fisik seseorang serta
gangguan berkembangnya kecerdasan, menurunya sisitem kekebalan tubuh, serta tingginya
kesakitan dan kematian. Tingkat konsumsi seseorang dapat mempengaruhi status gizi oaring
tersebut. Jika seseorang dapat memenuhi dan memperoleh zat gizi dengan baik dan dapat
digunakan secara efisien maka pertumbuhan fisik, kecerdasan, dapat berkerja lebih optimal. Status
gizi lebih dapat menimbulkan hal yang berbahaya pada tubuh karena tubuh memperoleh zat gizi
dalam jumlah berlebihan.(5)
Stunting dapat menghambat perkembangan fisik dan mental anak, dimana berkaitan dengan
meningkatnya risiko kematian dan kesakitan serta menghambat kemampuan pertumbuhan motorik
dan mental, produktivitas, penurunan intelektual, dan peningkatan risiko penyakit degeneratif di
masa mendatang.(6)
Bayi berusia 0-6 bulan hanya memerlukan Air Susu Ibu (ASI) saja sebagai
nutrisi utama. Setelah 6 bulan, bayi baru dapat diberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI).
MP-ASI diberikan atau mulai di perkenalkan pada bayi ketika umur balita diatas 6 bulan.(7)
Selain
berfungsi untuk mengenalkan jenis makan baru pada anak, MP-ASI juga dapat mencukupi
kebutuhan nutrisi bayi yang tidak dipenuhi oleh ASI saja, serta dapat membentuk daya tahan tubuh
dan perkembangan sistem imunologis anak terhadap makanan dan minuman.(8)
WHO
merekomendasikan pemberian ASI ekslusif 6 bulan pertama kehidupan dan dilanjutkan dengan
pengenalan MP-ASI akan tetapi ASI tetap dilanjutkan sampai usia 2 tahun.(9)
Balita dikatakan MP-ASI dini apabila balita tersebut diberikan makanan atau minuman selain
ASI sebelum balita berusia 6 bulan. Menurut Riskesdas (2010)(10)
proporsi pemberian MP-ASI dini
di Indonesia dapat dilihat berdasarkan ASI Parsial dan ASI predominan. Persentase pemberian ASI
parsial sebesar 83,2%. Sedangkan persentase pemberian ASI predominan sebesar 1,5%. Menurut
penelitian Teshome anak yang diberi MP-ASI dini berisiko untuk mengalami kejadian stunting.
Berdasarkan penelitian Rahayu (2011)(11)
menyatakan bahwa pemberian MP-ASI dini bisa
menyebabkan risiko stunting karena bayi belum memiliki saluran pencernaan sempurna sehingga
lebih mudah terkena penyakit infeksi seperti diare dan ISPA. Oleh karena itu, berdasarkan uraian
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 3
latar belakang diatas maka perlu dilakukannya penelitian untuk mengetahui Pengaruh Pemberian
MP-ASI Dini Dengan Kejadian Stunting Pada Balita 24-59 Bulan Di Indonesia (Analisis Data
IFLS 5).
METODE
Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional. Populasi penelitian ini adalah
seluruh responden yang berada di 13 Provinsi di Indonesia yang berhasil ditemui saat pencacahan
dan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian sebanyak
1.006 responden. Variabel dependen dalam penenlitian ini adalan kejadian stunting. sedangkan
variabel independen dalam penelitian ini adalah pemberian MP-ASI Dini. Variabel confounding
meliputi ASI eksklusif, status imunisasi, berat badan lahir, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, jenis
kelamin balita, penyakit infeksi, status ekonomi keluarga, tinggi badan ibu, wilayah tempat tinggal
dan ketersediaan air bersih. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik
multistage random sampling dengan kriteria inklusi yaitu balita usia 24-59 bulan dan ibu balita
yang merupakan responden IFLS tahun 2014 dan kriteria eksklusi meliputi adanya missing data,
ibu balita yang menjawab tidak tahu dan data responden yang tidak singkron. Analisis data
dilakukan secara univariat, analisis bivariat dengan menggunakan ujichi-square dan analisis
multivariat menggunakan uji regresi logistik ganda dengan model faktor risiko.
HASIL PENELITIAN 1. Analisis Univariat
Analisis uni variat dilakukan untuk mengetahui distribusifrekuensi respondenberdasarkan
variabel independen utama, variabel dependen dan variabel confounding.
Tabel 1.
Distribusi Frekuensi Variabel yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Balita 24-59
Bulan di Indonesia
Variabel Total Responden
n %
Variabel Dependen
Kejadian Stunting Stunting 440 43,8
Normal 566 56,2
Variabel Independen Utama
Pemberian MP-ASI Dini MP-ASI Dini 785 78
Tidak MP-ASI Dini 221 22
Variabel Confounding
Pemberian MP-ASI Dini MP-ASI Dini 785 78
Tidak MP-ASI Dini 221 22
Riwayat ASI Eksklusif
Tidak ASI Eksklusif 785 78 ASI Eksklusif 221 22
Status Imunisasi
Tidak Imunisasi 464 46,1 Imunisasi Tidak Lengkap 103 10,3
Imunisasi Lengkap 439 43,6
Riwayat BBLR
BBLR 82 8.2 Tidak BBLR 924 91.8
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 4
Variabel Total Responden n %
Jenis Kelamin Laki-laki 531 52,8
Perempuan 475 47,2
Riwayat Penyakit Infeksi (Diare dan
ISPA)
Pernah 294 29,2
Tidak Pernah 712 70,8
Tinggi Badan Ibu
Pendek (<150cm) 356 35,6 Normal (≥ 150 cm) 648 64,4
Pendidikan Ibu
Rendah 217 21,6
Menengah 651 64,7 Tinggi 138 13,7
Pekerjaan Ibu
Tidak Bekerja 492 48,9
Bekerja 514 51,1
Status Ekonomi
Rendah 545 54,2
Tinggi 461 45,8
Wilayah Tempat Tinggal Pedesaan 459 45,7
Perkotaan 547 54,3
Ketersediaan Air Bersih
Tidak Tersedia 11 1,1 Tersedia 995 98,9
Berdasarkan tabel1 hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Distribusi kejadian stunting pada
balita 24-59 bulan dimana 43,8% balita mengalami stunting (-3SD s/d <-2SD). Mayoritas balita
dengan MP-ASI dini (78%) dengan jumlah 785 balita. Sebanyak 78% balita memiliki riwayat tidak
ASI eksklusif. Sebagian besar balita dengan status imunisasi yang tidak imunisasi(46,1%).
Mayoritas balita dengan riwayat tidak BBLR (91,8%). Mayoritas anak balita pada penelitian ini
adalah balita berjenis kelamin laki-laki (52,8%). Sebagian besar kelompok balita tidak memiliki
riwayat penyakit infeksi (70,8%). Mayoritas proporsi kelompok ibu dengan tinggi badan normal (≥
150 cm) (64,4%). Pendidikan ibu balita yang paling dominan pada penelitian ini termasuk dalam
kategori menengah (SMP, SMA dan Sederajat) dengan frekuensi sebanyak 651 ibu. Proporsi status
bekerja mayoritas pada kelompok ibu yang bekerja (51,1%). Mayoritas keluarga memiliki status
ekonomi keluarga yang rendah (54,2%). Sebagian besar wilayah tempat tinggal keluarga adalah di
wilayah perkotaan (54,3%) keluarga balita. Mayoritas proporsi keluarga yang memiliki air bersih
(98,9%).
2. Analisis Bivariat
Analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara masing-masing variabel
independen (variabel independen utama dan variabel perancu) dengan kejadian stunting.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 5
Tabel 2. Hubungan Antara Variabel Indepeden Utama dan Variabel Perancu dengan
Kejadian Stunting
Variabel
Kejadian Stunting
p-value PR
95%CI Stunting Normal
n % n %
Pemberian MP-ASI Dini MP-ASI Dini 368 46,8 417 53,2
<0,0001 1,427
(1,262-1,613) Tidak MP-ASI Dini 73 32,8 148 67,2
Riwayat ASI Eksklusif
Tidak ASI Eksklusif 368 46,8 417 53,2 <0,0001
1,427
(1,262-1,613) ASI Eksklusif 73 32,8 148 67,2 Status Imunisasi
Tidak Imunisasi 237 51,2 226 48,8 <0,0001 2,091
(1,797-2,434)
Imunisasi Tidak Lengkap 56 54,4 47 45,6 <0,0001 2,375
(1,956-2,883) Imunisasi Lengkap 147 33,4 292 66,6
Berat Badan Lahir
BBLR 45 54,6 37 45,4 0,002
1.275
(1,116-1,457) Normal 395 42,8 528 57,2
Pendidikan Ibu
Rendah 102 46,9 115 53,1 0,007 1,404
(1,100-1,792)
Menengah 285 43,8 366 56,2 0,043 1,236
(1,007-1,518)
Tinggi 53 38,6 84 61,4
Pekerjaan Ibu
Tidak Bekerja 224 45,5 268 54,5 0,042
1,082
(1,003-1,167) Bekerja 216 42,1 298 57,9
Jenis Kelamin Balita
Laki-laki 242 45,6 289 54,4 0,036
1,096 (1,006-1,193) Perempuan 198 41,6 277 58,4
Status Ekonomi Keluarga
Rendah 250 46 294 54 0,013
1,117 (1,024-1,218) Tinggi 190 41,1 271 58,9
Tinggi Badan Ibu
Pendek 189 52,8 169 47,2 <0,0001
1,362
(1,247-1,488) Normal 251 38,8 397 61,2
Riwayat Penyakit Infeksi
Pernah 131 44,5 163 55,5 0,633
1,025
(0,927-1,133) Tidak Pernah 309 43,4 403 56,6
Wilayah Tempat Tinggal
Pedesaan 205 44,6 255 55,4 0,402
1,035
(0,955-1,121) Perkotaan 235 43,1 311 56,9
Ketersediaan Air Bersih
Tidak Tersedia 4 33,8 7 66,2 0,090
0,770
(0,554-1,071) Tersedia 436 43,9 559 56,1
*Signifikan :p-value < 0,05
Berdasarkan tabel 2 hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa terdapat 9 variabel yang
kurang dari nilaialpha(0,05) dan terdapat 3 variabel yang lebih dari alpha(0,05). Sehingga dapat di
simpulkan ada hubungan antara variabel pemberian MP-ASI dini, ASI eksklusif, status imunisasi,
berat badan lahir, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, jenis kelamin balita, status ekonomi keluarga, dan
tingggi badan ibu dengan kejadian stunting. Tidak terdapat hubungan antara variabel riwayat
penyakit infeksi, wilayah tempat tinggal dan ketersediaan air bersih dengan kejadian stunting. Hasil
analisis statistik diatas menunjukkan nilai PR variabel independen utama sebesar 1,427. Angka
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 6
tersebut menunjukkan bahwa obesitas merupakan faktor risiko kejadian stunting dengan 95% CI
berkisar antara 1.262 sampai dengan 1,613. Begitu juga dengan variabel-variabel lain yang hampir
menunjukkan hasil serupa. Variabel ASI eksklusif, status imunisasi, berat badan lahir, pendidikan
ibu, pekerjaan ibu, jenis kelamin balita, status ekonomi keluarga, tinggi badan ibu, riwayat penyakit
infeksi, wilayah tempat tinggal menunjukkan adanya risiko untuk mengalami kejadian stunting,
dengan masing-masing PR 1,427;2,091;1,275;1,404;1,236;1,082;1,096;1,117;1,362;1,025;1,035.
Variabel ketersediaan air bersih justru menunjukkan hasil protektif dengan PR = 0,770.
3. Analisis Multivariat
Hasil analisis multivariat memaparkan hasil hubungan antara pemberian MP-ASI dini
dengan kejadian stunting setelah dikontrol dengan variabel confounding.
Tabel 3. Final Model Analisis Multivariat Hubungan Antara Pemberian MP-ASI Dini
Dengan Kejadian Stunting
Variabel p-value Adjusted PR 95% CI
Lower Upper
MP-ASI Dini <0,0001 1,873 1,529 2,293
BBLR 0,030 1,466 1,038 2,069 Tinggi Badan Ibu <0,0001 1,723 1,444 2,055
Status imunisasi
Tidak Imunisasi <0,0001 2,187 1,862 2,568
Imunisasi Tidak Lengkap <0,0001 2,424 1,997 2,941 Imunisasi Lengkap(reff)
*Signifikan :p-value < 0,05
Berdasarkan tabel 3 hasil analisis diatas, diketahui bahwa terdapat hubungan antara pemberian MP-
ASI dini dengan kejadian stunting setelah dikontrol dengan variabel berat badan lahir, tinggi badan
ibu, dan status imunisasi PR 1,873;95% CI = 1,529-2,293.
PEMBAHASAN
Status gizi masa lampau di gambarkan dengan Indeks antropometri TB/U. Jika anak
tersebut pendek,artinya ada indikasi rendahnya kualitas dan kuantitas asupan makanan dalam
rentan waktu yang relatif lama. Rendahnya TB/U pada anak pada anak yang lebih tua (di atas 3
tahun) merefleksikan kegagalan pertumbuhan (stunted), sedangkan lebih muda (di bawah 2-3
tahun) di negara berkembang juga merefleksikan kegagalan proses pertumbuhan selanjutnya
(stunting). Hal yang perlu diperhatikan adalah gangguan pertumbuhan dimulai sejak bayi yang
dipengaruhi oleh kondisi spesifik yang bervariasi antar populasi. Anak dengan pertumbuhan
pendek pertumbuhannya sulit untuk dikejar namun jika anak-anak tersebut dapat diberikan asupan
makanan yang baik serta lingkungan tersebut dapat memgolah sanitasi lingkungan dengan bersih
maka akan terjadi perubahan pertumbuhan ada anak-anak tersebut.(12)
Berdasarkan data WHO dalam Kemenkes RI (2016)(13)
diperkirakan sebanyak 162 juta anak
didunia mengalami masalah stunting pada tahun 2012, di Asia anak pendek hidup sebanyak 56%
dan 36% di Afrika bagian Timur dan Selatan. Kejadian stunting pada balita lebih banyak terjadi di
Negara berkembang dengan prevalensi kejadian sebesar 30% (UNICEF, 2009)(14)
. Dibandingkan
dengan beberapa Negara tetangga, prevalensi balita pendek di Indonesia masih tinggi yaitu
sebanyak 7,5 juta balita dibandingkan dengan Myanmar (35%), Vietnam (23%), Malaysia (17%),
Thailand (16%), dan singapura (4%) (UNSD, 2014)(4)
. Hasil Riskesdas tahun 2013 bahwa
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 7
prevalensi kejadian stunting sebesar 37,2% dan terjadi peningkatan dari tahun 2010 sebesar
1,6%.(15)
Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa proporsi anak balia yang mengalami stunting
yaitu sebanyak 43,8% dengan jumlah 440 balita dari 1.006 balita. Sedangkan balita yang memiliki
status gizi normal sebesar 56,2% dengan jumlah 566 balita dari 1.006 balita yang masuk kedalam
penelitian. Hasil penelitian ini mengatakan terdapat hubungan antara pemberian MP-ASI dini
dengan kejadian stunting setelah dikontrol dengan variabel berat badan lahir, tinggi badan ibu dan
status imunisasi. Hasil tersebut diperkuat oleh penelitian Hendra (2018), dimana anak yang
diberikan MP-ASI dini 6,5(95%CI 1,8-22,9) kali lebih berisiko untuk mengalami gangguan
pertumbuhan dibandingkan anak yang diberikan MP-ASI tepat waktu.(16)
Sejalan dengan hal
tersebut, penelitian Nova (2018), menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara variabel
pemberian MP-ASI dengan kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan di puskesmas Lubuk
Buaya.(17)
Penelitian ini sesuai dengan teori Depkes (2005), yang mengatakan bahwa terganggunya
pertumbuhan pada awal masa kehidupan bayi antara lain disebabkan karena kekurangan gizi sejak
bayi. Dalam pemberian makanan pada bayi harus memperhatikan frekuensi pemberian, ketepatan
waktu pemberian, jumlah bahan makanan dan cara pembuatannya. Adanya kebiasaan pemberian
makanan bayi yang tidak tepat antara lain yaitu pemberian makanan yang terlalu dini, makanan
yang diberikan tidak cukup dan frekuensi yang kurang.(18)
Makanan pendamping ASI (MP-ASI)
memiliki peranan penting dalam memenuhi dan melengkapi kebutuhan zat-zat gizi anak usia 6-24
bulan karena ASI sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi untuk mencapai tumbuh kembang
yang optimal. Pengetahuan ibu yang rendah tentang pemberian MP-ASI dan pemberian MP-ASI
yang dilakukan secara tidak tepat dan benar dapat menyebabkan masalah gizi sepertigangguan
pertumbuhan dan perkembangan serta gizi kurang.(19)
Menurut Lestari (2014), anak yang diberikan MP-ASI dini memiliki risiko menjadi stunting
6.54 kali dibandingkan dengan anak yang diberikan MP-ASI sesuai dengan umur seharusnya.
Penelitian ini menujukkan bahwa terdapat hubungan antara kegagalan ASI eksklusif dengan
pemberian MP-ASI dini. Ibu yang tidak memberikan ASI secara eksklusif biasanya memberikan
makanan lain sebagai pengganti ASI. MP-ASI yang biasa diberikan berupa pisang, bubur saring,
susu formula, dan biskuit. Berdasarkan kematangan fisiologis dan kebutuhan gizi, pemberian
makanan selain ASI kepada bayi sebelum usia 6 bulan akan menyebakan penyakit diare, alergi dan
penyakit lainnya. Hal ini disebabkan karena saluran pencernaan bayi belum siap untuk mencerna
makanan selain ASI.(20)
Berat badan lahir dibagi menjadi dua kategori yaitu normal jika berat badan lahir ≥2500
gram dan berat badan lahir rendah (BBLR) jika berat badan lahir <2500 gram (kemenkes, 2010).
Berdasarkan hasil analisis univariat pada penelitian ini menunjukkan bahwa dari 1.006 balita,
sebagian besar balita tidak memilikik riwayat BBLR dengan frekuensi sebesar 924 balita atau
setara dengan 91,8%. Hasil bivariat menunjukkan bahwa proporsi balita dengan riwayat BBLR
yaitu sebanyak 54,6% yang mengalami stunting, sedangkan balita dengan riwayat tidak BBLR
sebesar 42,8% yang mengalami stunting. Hasil analisis multivariat terlihat bahwa terdapat
hubungan yang signifikan antara berat badan bayi lahir terhadap kejadian stunting pada balita
dengan p-value sebesar 0,030 dengan adjusted PR 1,466 (95% CI 1,038-2,069), artinya balita
dengan riwayat BBLR berpeluang lebih besar 1,466 kali untuk mengalami stunting dibandingkan
balita dengan berat badan lahir normal. Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian Supriyanto
(2017), dimana anak yang memiliki riwayat BBLR berisiko 6,16 kali lebih besar (95% CI 3,007-
12,656) untuk mengalami stunting dibandingkan dengan anak yang tidak memiliki riwayat
BBLR.(21)
Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Oktarina (2013), menunjukkan bahwa anak
dengan BBLR berpeluang 1,31 kali (95% CI 1,02-1,68) kali lebih besar dibandingkan dengan anak
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 8
yang memiliki berat badan lahir normal.(22)
Arifin (2015), menjelaskan bahwa anak dengan riwayat
BBLR jika diiringi dengan konsumsi makanan yang tidak adekuat dan pelayanan kesehatan yang
tidak layak maka akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan dan menghasilkan anak stunting.
Selain itu, bayi yang lahir dengan berat badan rendah biasanya akan diberikan susu formula
tambahan khusus bayi dengan berat badan lahir rendah. Sehingga hal tersebut dapat membuat
gagalnya pemberian ASI eksklusif kepada bayi.(23
)
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nadiyah (2014), tinggi badan ibu yang <150
cm berisiko 1,768 kali (95% CI 1,205-2,594) lebih besar untuk melahirkan anak stunting.(6)
hal
tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rahayu (2015), bahwa tidak terdapat
pengaruh inggi badan ibu terhadap kejadian stunting.(11
) Berdasarkan penelitian tersebut
menunjukkan bahwa kejadian stunting pada balita disebabkan melalui genotif pendek yang
diturunkan oleh ibunya (Aisyah, 2015)(24
). Menurut Direktur Gizi Masyarakat Kemenkes RI bahwa
masalah stunting tidak hanya disebabkan oleh kurangnya gizi dari seorang anak, masalah genetik
juga dapat menyebabkan stunting, dimana genetik menyumbangkan faktor risiko sebesar 26%.
Tampilan fenotip yang muncul tergantung pada ekspresi genetik manusia, serta merupakan faktor
yang diturunkan kepada anak yang berkaitan dengan kejadian stunting (Kusuma, 2013)(25
). Namun,
apabila sifat pendek orang tua disebabkan oleh masalah gizi maupun patalogis maka sifat pendek
tersebut tidak diturukan pada anaknya.
Hasil ini menunjukkan bahwa anak dengan status tidak imunisasi lebih berisiko 2,187
mengalami stunting dibandingkan dengan anak dengan status imunisasi lengkap. Selanjutnya, anak
dengan status imunisasi tidak lengkap berpeluang 2,424 kali lebih besar untuk mengalami stunting
dibandingkan dengan anak yang status imunisasi lengkap. Penelitian sebelumnya mengemukakan
hasil yang serupa yaitu balita yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap berisiko 3,5 kali
mengalami stunting dibandingkan dengan anak balita yang mendapatkan imunisasi lengkap
(Hendra, 2013).(26
) Imuniasi erat kaitannya dengan peningkatan daya tahan tubuh dan resistensi
terhadap penyakit. Namun, anak dengan imunisasi dasar lengkap jika tidak diimbangi secara
maksimal dengan faktor lain seperti asupan makanan yang baik maka akan tetap mengganggu
kekebalan dan ketahanan tubuh, hal tersebut akan meningkatkan kerentanan anak untuk mengalami
stunting. Selain itu, kualitas vaksin juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi
manfaat serta efektivitas pemberian imunisasi (Hayyudini, 2017).(27
)
KESIMPULAN DAN SARAN
Prevalensi kejadian stunting pada balita 24-59 bulan di Indonesia dalam penelitian ini adalah
sebesar 43,8%. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa terdapat 9 variabel yang berhubungan
secara signifikan dan terdapat 3 variabel yang tidak memiliki hubungan atau tidak signifikan.
Sehingga dapat di simpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara variabel pemberian MP-
ASI dini, ASI eksklusif, status imunisasi, berat badan lahir, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, jenis
kelamin balita, status ekonomi keluarga, dan tingggi badan ibu dengan kejadian stunting. Tidak
terdapat hubungan antara variabel riwayat penyakit infeksi, wilayah tempat tinggal dan
ketersediaan air bersih dengan kejadian stunting. Berdasarkan hasil analisis multivariat, diketahui
bahwa terdapat hubungan antara pemberian MP-ASI dini dengan kejadian stunting setelah
dikontrol dengan variabel berat badan lahir, tinggi badan ibu, dan status imunisasi.
Saran untuk penelitian ini ialah adanya kerjasama lintas sektor menagani masalah gizi
masyarakat, kepada tenaga kesehatan lebih memberi dukungan kepada orang tua agar terus tetap
memberikan ASI eksklusif hingga bayi barusia 6 bulan, adanya kerja sama orang tua untuk
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 9
memperhatikan status gizi anak, serta melakukan deteksi dini dengan mengukur tinggi badan anak
secara rutin agar pertumbuhan kembang anak dapat diapantau.
DAFTAR PUSTAKA
1. Purwandini K. Pengaruh Pemberian Mikronutrient Sprinkle Terhadap Perkembangan
Motorik Anak Stunting Usia 12-36 Bulan. J Nutr Coll. 2013;2:147–63.
2. Kartikawati. Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunted Growth Pada Anak Balita di
Wilayah Kerja Puskesmas Arjasa Kabupaten Jember. Univesitas Jember; 2012.
3. Millenium challenge account-indonesia. Stunting dan masa depan indonesia [Internet].
2014. Available from: http://mca-indonesia.go.id/wp-
content/uploads/2015/01/Backgrounder-Stunting-ID.pdf.
4. UNSD. Nutrition Assessment For 2010 New Project Design [Internet]. 5 Januari 2019.
2014. Available from: www.indonesia.usaid.gov
5. Emalia., Fatmalina F. AR. Hubungan Asupan Gizi, Pengetahuan dan Stimulasi ibu dengan
Tumbuh Kembang Anak Prasekolah TK Handayani dan TK Teratai 26 Ilir Kecamatan Bukit
Kecil Palembang 2014. J Ilmu Kesehat Masy. 2015;Vol. 6. No.
6. Nadiyah N dan M. Faktor Risiko Stunting pada Anak Usia 0-23 Bulan di Provinsi Bali,
Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. J Gizi dan Pangan. 2014;9.
7. Departemen Kesehatan RI. Pola Makan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). Jakarta; 2009.
8. Kementerian Kesehatan RI. Pusat Data Dan Informasi Situasi dan Analisis ASI Eksklusif.
Jakarta; 2017.
9. WHO (World Health Organization). Feeding And Nutrition of Infants and Young Children.
2014.
10. Riset Kesehatan Dasar. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian
Kesehatan. Jakarta; 2010.
11. Rahayu Atika dkk. Riwayat Berat Badan Lahir dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia
Bawah Dua Tahun. J Kesehat Masy Nas. 2015;20.
12. Destriatania S. Analisis Praktik Menyusui, Penyakit infeksi dan Faktor Sosiodemografi
Terhadap Pertumbuhan Linear Anak Usia 12-60 Bulan di Kecamatan Indralaya Kabupaten
Ogan Ilir. J Ilmu Kesehat Masy. 2013;Vol. 4. No.
13. Kementerian Kesehatan RI. Pusat Data Dan Informasi Situasi Balita Pendek. Jakarta; 2016.
14. UNICEF. TRACKING Progress on Child and Maternal Nutrition a Survival and
Development Priority [Internet]. www.unicef.org/publications. 2009. Available from:
www.unicef.org/publications
15. Riset kesehatan Dasar. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian
Kesehatan RI. Jakarta; 2013.
16. Hendra AAR. Pemberian ASI dan MP-ASI Terhadap Pertumbuhan Bayi 6-24 Bulan. J
Kedokt Syiah Kuala. 2018;17 No.1.
17. Nova M dan OA. Hubungan Berat Badan, ASI Eksklusif, MP-ASI Dan Asupan Energi
dengan stunting pada Balita Usia 24-59 Bulan di Puskesmas Lubuk Buaya. J Kesehat
Perintis. 2018;5 No. 1.
18. Departemen Kesehatan RI. Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan ASI Eksklusif bagi Petugas
Puskesmas. Jakarta; 2005.
19. Nurmaliani, R., Fatmalina F. RM. Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu dan Pemberian
Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan di Kelurahan Kuto Batu Kota
Palembang. J Ilmu Kesehat Masy. 2010;Vol.1. No.
20. Lestari, w., Margawati A. Faktor risiko stunting pada anak umur 6-24 bulan di kecamatan
penanggalan kota subussalam provinsi aceh. J Gizi Indones. 2014;3 No.1:37-45.
21. Supriyanto, Y., Paramashanti, B.A., & Astiti D. Berat Badan Lahir Rendah Berhubungan
Dengan Kejadian Stuntingpada Anak Usia 6-23 Bulan. J Gizi Dan Diet Indones. 2017;Vol.5
No.1:23–30.
22. Oktarina, Z dan Sudiarti T. Risk Factor of Stunting Among Toddlers (24-59) at Sumatera.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 10
Nutr Food J. 2013;Vol.8 No.3:175–80.
23. Arifin dan H. Analisis Sebaran Dan Faktor Risiko Stunting Pada Balita Di Kabupaten
Purwakarta. 2012;Vol.2 No.3.
24. Aisyah S. Perkembangan Dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia Dini. Jakarta:
Universitas Terbuka; 2010.
25. Kusuma K dan N. Faktor Risiko Kejadian Stunting pada Anak Usia 2-3 Tahun (Studi di
Kecamatan Semarang Timur). Diponegoro University; 2013.
26. Hendra A MA dan HA. Kajian Stunting pada Anak Balita ditinjau dari Pemberian ASI
Eksklusif, MP-ASI, Status Imunisasi, dan Karakteristik Keluarga di Kota Banda Aceh. J
Kesehat Ilm Nasuwakes. 2013;Vol.6. No.:169–84.
27. Hayyudini, D dan Dharmawan Y. Hubungan Karakteristik Ibu, Pola Asuh dan Pemberian
Imunisasi Dasar Terhadap Status Gizi Anak Usia 12-24 Bulan (Studi di Wilayah Kerja
Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang Tahun 2017). J Kesehat Masy. 2017;Vol.5
No.4:788–800.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 11
TOLUENE EXPOSURE MANAGEMENT FOR PRINTING MACHINE
OPERATORS IN OFFSET PRINTING COMPANIES
Widya Haris Saraswati
1, Mona Lestari
2*, Novrikasari
3, Dini Arista Putri
4, Anita Camelia
5
1Students of the Faculty of Public Health, Sriwijaya University
2,3,5Section of Occupational Health and Safety, Faculty of Public Health, Sriwijaya University
4Section of Environmental Health, Faculty of Public Health, Sriwijaya University
Jl. Palembang Prabumulih KM 32, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan Corresponding email: [email protected]
ABSTRACT
Printing ink that were comonly usef in offset priinting company contains organic pigments. The organic
pigments are made from aromatic hydrocarbons such as benzene its derivatives. In short term, exposure to
organic solvents can cause dizziness, nausea, and sleepiness. This study purpose is to analyze the
management toluene exposure in printing company towards the printing machine operators. The method of
this study is qualitative description. To check the data validity test uses data triangulation techniques. The
total research informants numbered nine people consisting of seven printing machine operators as key
informants and two managers as ordinary informants. The results this research obtained show that seven
printing machine operators still do not understand the risks of toluene exposure in their work place, the lack
of supervision from the printing manager and the absence of regulations or sanctions regarding the use of
self protection gear play parts to why the printing press operators still do not fully understand the benefit of
wearing masks or other personal protective equipment while working. In conclusion, 7 out of 9 informants
experienced symptoms of being exposed to toluene due to lack of knowledge of toluene exposure which cause
lack of personal protective equipment uses. The lack of regulations regarding the use of protective gear also
play part in this. To fix the lack of control of personal protective equipment regulation in offset printing
company, managers are required to make regulation of personal protection in printing work place and
provide the appropriate personal protective equipment.
Keywords: Offset print ink, personal protective equipment (PPE), toluene
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 12
INTRODUCTION
Printing is an industry that uses technology to produce printed products. The copies of the
printing industry results can be in the form of words or pictures printed on paper, cloth, and other
media. Every day, billions of printed product are produced, including books, calendars,
newspapers, posters, invitations, and other materials.1 Printing uses large amounts of flammable
organic solvents and uses combustible materials such as paper, cloth, plastic when working.
The work process in printing is generally divided into four steps, namely: pre-press, make-
ready, press, and post-press. A pre-press operation is a process that transfers print design data to a
printing machine.2 This operation involves chemical and physical processes such as exposure to
ultraviolet (UV) light, photoengraving or laser printing, development, and further processing.
Make-ready is a print preparation process where the printing machine is adjusted with the printing
process that will be done. The Press step is the printing process. Finally, post-press is a finishing
process such as binding, pasting, and so on. Printing uses large amounts of flammable solvents and
uses combustible materials such as paper, cloth, plastic when working. Pigments are dyes that are
insoluble, have larger grains, are more resistant to light, heat, and chemicals. Pigments are
commonly used in offset inks such as gaseous inorganic pigments and soot. Pigments derived from
natural dyes are dyes that are naturally present in plant and animal tissues.3
Exposure to organic solvents can be through inhalation, oral, and contact. Long-term health
effects that can be caused due to exposure to benzene and its derivatives are damage to internal
organs such as the liver, kidneys and lungs, and so on. Organic solvents can also cause damage to
the central nervous system with effects such as drowsiness, impaired body coordination, decreased
focus of mind and vision. Organic solvents (thinners) consist of various types of organic substances
such as aromatic hydrocarbons such as benzene and its derivatives, aliphatic hydrocarbons (for
example n-hexane), chlorinated aliphatic hydrocarbons (for example chloroform, CCl4), alcohols,
or glucose and ether.4 Time-weighted Average Threshold Value (NAV) of chemicals in the air of
the workplace, with a number of working hours of 8 hours per day or 40 hours per week, states that
benzene is included in the group. A2 (category of carcinogenic chemicals for humans) has TLV of
10 ppm or 32 mg/m3 of benzene in the air.
5
Exposure to organic solvents within the scope of work in printing can cause dizziness,
nausea, and irritation, and long-term exposure can lead to cirrhosis (decreased liver function),
decreased kidney function, and nervous disorders.4 In a study conducted by Fatmawati, as many as
58.5% of printing operators in the Rappocini District of Makassar City who did not use personal
protective equipment (PPE) while working had dermatitis disorders.6
The purpose of this study was to analyze the self-protection management of printing machine
operators against exposure to toluene in the Palembang city offset printing press. Other factors that
can influence self-protective behavior by printing workers can be analyzed using Lawrence Green's
theory, namely predisposing factors (knowledge, perceptions, motivation, attitudes), enabling
factors (supporting facilities), and reinforcing factors (policy, supervision, regulations).7
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 13
METHOD
This research use descriptive qualitative method with in-depth interviews as a method of data
collection. The data validity test used data triangulation technique. This study used a qualitative
research design. Information obtained is usually in the form of words or text. Data in the form of
words or text is then analyzed. The results of the analysis can be in the form of a description or
description or it can be in the form of themes. From these data, interpretation is made to capture the
deepest meaning. After that, a personal reflection (self-reflection) is made and describes it with
other scientific studies previously made. The final results of the qualitative research are written in
the form of a written report. The report is somewhat flexible because there are no standard
provisions on the structure and form of the qualitative research report.
Informants in this qualitative research are divided into two; key informants and supporting
informants. The main criteria for key informants are people who are willing to share concepts and
knowledge with researchers and can communicate with researchers. Researcher data collection
starts with key informants to get a complete and comprehensive picture of the problem being
observed.8
The research was carried out in two offset printers in Palembang City, namely; X
Printing Company and Y Printing Company. The key information in this study is divided into two;
7 printing machine operators as key informants and 2 managers as supporting informants. The
informants are willing to share concepts and knowledge with researchers and can communicate
with researchers through in-depth interviews, which supported by observation check-lists and
documentations in form of photos, recording, and library study sources.
RESULT 1. Source of Toluene Exposure
The main sources of toluene exposure at X Printing Company and Y Printing Company are
derived from inks and solvents used as ink thinners. The source of benzene vapor in printing came
from ink droplets in the open roll cylinder of the printing machine, printed products, ink spills, and
a funnel for inserting ink into the funnel or jerry can.9 The source of toluene orr any other benzene
derivatives exposure is identified by looking at the presence of toluene in the ink or solvent
ingredients. The ink material ingredients can be seen from the ink patents.
X Printing Company using KONICA ink which produced by Konica Minolta, a company
that focuses on the printing industry. On patent filed behalf of the company Konica Minolta, fwith
patent code USOO7604.343B2. Konica Minolta company uses benzyl methacrylate, benzyl
acrylate, fluorobenzyl group, and other methozybenzyl group groups as solvent components of the
ink. Benzyl is a group of compounds with the formula C6H5CH2-, which is made from toluene
(C6H5-CH3), which is a benzene derivative compound.10
Meanwhile, Y Printing Company uses
Syner-G EX inks produced by the Sun Chemical company, which is a company that focuses on
producing inks and ink pigments. The patent filed by the Sun Chemical company entitled Energy
Curable Lithographic Inks Containing Lactic Acid Resins which was released in 2014 states that
the ink produced by Sun Chemical uses toluene, a derivative of the benzene group of compounds,
as a solvent.
Exposure to toluene within 30 to 60 minutes and below 200 ppm can cause acute symptoms
such as dizziness, nausea, drowsiness, tremors, and various respiratory symptoms such as nasal
discharge and tightness. breath. Acute effects on the upper respiratory system caused by exposure
to toluene generally appear 6 hours after exposure. In high doses such as 200 to 500 ppm, toluene
can cause loss of balance, loss of appetite, and memory loss.11
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 14
Table 1. Symptoms of Acute Toluene Exposure to Printing Machine Operators at Work
No. Name Symptoms
Headache Nausea Tremor Sleepiness Others
1. Hr - - - - -
2. Rp - - - - Shortness of
breath
3. Bm - - - - Often feel thirsty
while working
4. Fd √ - - - Coughing
5. Fth √ √ - - -
6. Fhr √ - - - Shortness of
breath
7. Ea √ √ - - -
8. Ftm √ - - - -
9. Ahm √ - - - Shortness of
breath
Table 2. Number of Informants Experiencing Acute Symptoms of Toluene Exposure
No. Type of informant Amount Number of Informants Experiencing Acute
Symptoms of Toluene Exposure
1. Key Informants 7 5
2. Supporting Informants 2 2
Total 9 7
The results of interviews at X Printing Company and Y Printing Company, show that as
many as 5 out of 7 key informants who work in the printing press room feel symptoms of dizziness,
nausea, and shortness of breath while working. Meanwhile, two managers who oversee the print
work process do not work in the machine work process but also feel dizzy because the manager's
workplace placed near the printing machine room. The total number of informants who felt acute
symptoms of exposure to toluene was 7 out of a total of 9 informants. Apart from symptoms of low
levels of toluene exposure such as dizziness, nausea, and tremors, 3 out of 9 informants also
admitted to experiencing shortness of breath while working. The attitudes observed by the
researchers were the regularity of printing machine operators in wearing PPE during 8 hours of
work and the correct way to use PPE.
2. Knowledge
Based on in-depth interviews with 9 informants, of the 7 printing machine operators as key
informants interviewed, one printing machine operator considered that wearing a mask or other
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 15
PPE while working in the printing room was not important because it could interfere with his work.
Printing machine operators who thought that the use of masks or other PPE was not important came
from Y Printing Company.
This is inversely proportional to the results of observations by researchers where all key
informants from Y Printing Company wore masks while working for seven days even though the
use of masks was only a few hours in the morning. Meanwhile, not all key informants from X
Printing Company wore masks during the seven-day observation. This is also inversely
proportional to where all the key informants from X Printing Company consider wearing masks to
be important, but two out of four key informants never wore masks during the seven days of
observation and claimed to have never worn masks from the start of work.
3. Attitudes of Workers in Wearing PPE at Work
The attitudes observed by the researchers were the regularity of printing machine operators
in wearing PPE during 8 hours of work and the correct way to use PPE. Data obtained from
observations for seven days at X Printing Company and Y Printing Company.
Table 3. Observations on the use of PPE for the printing machine operators from X Printing
Company
No. Attitudes observed Days
1 2 3 4 5 6 7
1. Using mask while working √ - - √ - √ √
2. Wearing industrial apron while working - - - - - - -
3. Wearing industrial gloves while working - - - - - - -
4. Wearing boots while working - - - - - - -
5. Using mask properly √ - - √ - √ √
6. Wearing industrial apron properly - - - - - - -
7. Wearing infustrial gloves properly - - - - - - -
8. Wearing boots properly - - - - - - -
Of the four key informants from X Printing Company, two key informants were never seen
wearing masks or other PPE while working. In addition, for seven days, there were three days
where the printing machine operator did not wear a mask at all. Printing machine operators only
wear masks when the smell of the printing press is strong due to heavy ink usage. The smell of ink
is strongest when black colored ink is used to color the blocking part (the part with pure colors, not
mixed with other colors) of the banner.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 16
Table 4. Observations on the use of PPE for the printing machine operators from Y Printing
Company
Nu. Attitudes observed Days
1 2 3 4 5 6 7
1. Using mask while working √ √ √ √ √ √ √
2. Wearing industrial apron while working - - - - - - -
3. Wearing industrial gloves while working - - - - - - -
4. Wearing boots while working - - - - - - -
5. Using mask properly √ √ √ √ √ √ √
6. Wearing industrial apron properly - - - - - - -
7. Wearing infustrial gloves properly - - - - - - -
8. Wearing boots properly - - - - - - -
Based on the results of observations made by researchers for seven days, the printing
machine operator of X Printing Company did not wear a mask every day but the printing machine
operator of Y Printing Company wore a mask every day in the seven days of observation. Apart
from masks, X and Y Printing Company did not provide any other PPE. No printing machine
operators wears a mask or other PPE for 8 hours of work. Almost all printing machine operators no
longer wear masks after 11 o'clock because of the hot afternoon temperatures in work place.
4. Availability of PPE at the Printing
Based on observations for 7 days, X and Y Printing Company provided masks for
employees, especially printing machine operators. X Printing Company provides one motorcycle
mask for each worker and Y Printing Company provides surgical masks every day. Apart from
masks, the printer never gives other PPE to printing machine operators such as gloves, aprons and
shoes.
5. Applicable Regulations in Printing Regarding the Use of PPE
Based on in-depth interviews with 9 informants, X and Y Printing Company do not have
permanent written regulations regarding the use of PPE in the print room. The two print managers
have reminded operators to wear masks while working but no one operator wears masks regularly.
6. Manager's Supervision of the Use of PPE in the Printing
Based on the results of observations for 7 days and in-depth interviews, one way to ensure
that printing machine operators wear masks while working is by monitoring the print manager.
Even with managers present every day at the printing press, workers still don't wear masks
regularly because of this. This is supported by the absence of permanent written regulations from
the printing director regarding the use of masks or PPE while working in the print room. Thus,
supervision still cannot be optimized in the printing press because there are no fixed regulations.
Especially for Y Printing Company, supervision from superiors and managers is much lax because
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 17
the print room has CCTV so that managers and superiors don't feel the need to directly supervise
employees' work.
DISCUSSION 1. Exposure to Toluene in Printing
According to Faisal, benzene and its derivatives are included in volatile organic compound
pollutants, which means they are hydrocarbon bond chain compounds.12
In printing, exposure to
benzene is primary air pollution because printing has a direct source of that exposure, such as paint
and oil. Benzene which is a carcinogenic compound has negative effects when inhaled directly. The
impact of benzene exposure can be acute, such as dizziness, nausea, and tremors.13
Whereas in the
long term, exposure to benzene and its derivatives can cause aplastic anemia where benzene can
damage the function of the spinal cord, liver, and kidneys.14
As a volatile compound, the upper
respiratory organs such as the nose, larynx, and throat are the first organs to be affected by long-
term exposure to toluene. In the long term, exposure to toluene can result in decreased function of
the upper respiratory tract consisting of the nose, throat, and larynx, and damage the nerves
associated with the sense of smell. In addition to decreased olfactory and lung function, long-term
exposure to toluene can result in decreased nerve function causing drowsiness, tremors, nystagmus
(involuntary eye movements), hearing loss, and vision problems. Apart from the lungs and nerves,
long-term exposure to benzene and its derivatives is also speculated to cause liver and kidney
disorders.15
The results of interviews with informants from X and Y Printing Company showed that
almost all informants, both printing machine operators and managers, stated that they had
experienced mild symptoms of exposure to benzene or toluene while working. Symptoms of low or
acute exposure to toluene include dizziness, nausea, and tremors, as well as upper respiratory
system disorders such as shortness of breath or nasal discharge.
The number of informants who experienced mild or acute symptoms caused by exposure to
toluene was 7 out of a total of 9 informants. Some workers claim that they no longer feel dizzy
after getting used to the smell of ink and solvents, but working hours and workplaces, and
unchanging sources of exposure indicate that workers remain exposed to while working in a print
shop. Two managers who oversee the print work process do not participate in the work, in the
machine work process but also feel dizzy because the manager's workplace is near the machine
room.
The symptoms of dizziness and nausea felt by employees of X and Y Printing Company are
in line with the research of Febriantika which examined the impact of benzene exposure on printing
employees in Makassar. The results of research by Febriantika show that at low levels, exposure to
benzene can cause dizziness and drowsiness, fast heartbeats (tremors), headaches, and loss of
balance.16
This is also in accordance with the Benzene Guidelines which states that the acute effects
of exposure to benzene and its derivatives are dizziness, headaches, drowsiness, tremors, and loss
of consciousness. The effects of benzene exposure can increase when benzene is mixed with
alcohol which can increase the level of toxicity also states that there are no standardized guidelines
for dealing with benzene exposure through the air.13
According to the Agency for Toxic Substances
and Disease Registry11
, the acute symptoms of exposure to toluene through breathing are headache,
dizziness, and drowsiness. Exposure to toluene through the skin can cause irritation, it also applies
to the eyes and can cause poisoning if swallowed. There is no standardized medical treatment to
treat toluene poisoning. To overcome the acute effects of toluene exposure such as dizziness,
nausea, and drowsiness, it can be overcome by staying away from the source of exposure and
breathing clean air until the acute symptoms disappear.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 18
2. Knowledge
In Festinger's Dissonance Theory, an individual always tries to balance himself to behave in
accordance with the knowledge he has. Dissonance (imbalance) occurs because of a conflict within
an individual who tries to adjust himself to the knowledge he gets in the environment he is in. In
other words, the mismatch of a person's actions with the environment he is in is caused by
inadequate knowledge or environment so that a person has difficulty adapting.
The mismatch of a person's behavior in an environment or system can be corrected by
providing knowledge that is appropriate to the environment and the individual's job is located. In
other words, the knowledge provided to printing machine operators must be appropriate to field
conditions where exposure to benzene causes workers to wear PPE.
The results of interviews with printing machine operators as key informants at X and Y
Printing Company show that all printing machine operators understand their work as print machine
operators but not all printing machine operators know and understand the risk of toluene exposure
and the importance of wearing PPE to minimize exposure risks.
In accordance with the theory of Dissonance Festinger, all key informants understand their
duties as printing machine operators because they can explain their duties as printing machine
operators, but not all operators know the risks of exposure to benzene or know that wearing PPE
while working is important. All printing machine operators also know basic PPE such as masks and
their functions. However, two out of seven printing machine operators interviewed never wore
masks or other PPE at work because they felt wearing masks at work was unnecessary and could
interfere with work in the printing room. This is because two out of seven printing machine
operators do not understand the dangers of exposure to toluene while working in a printer even
though they understand the function of masks. This incident shows dissonance in Festinger's theory
that the printer operator's lack of knowledge of exposure to toluene in the print room has resulted in
printing machine operators not using personal protective equipment in an environment or situation
that requires the use of personal protective equipment.
This is in line with Hidalgo's A research, which examines the dissonance that occurs in-
market consumers towards organic food products, showing that market consumers do not buy
organic food products even though they are able to buy organic food ingredients and already know
the benefits of these organic food products. This phenomenon occurs due to a lack of consumer
understanding of the positive impact of organic foodstuffs on the environment and health. Hidalgo
concluded that knowledge is one of the main keys that can cross this dissonance. By providing
education about the benefits of organic food ingredients, this dissonance can be overcome.17
Likewise, the research of Jamitko which shows that the level of knowledge shows a significant
relationship with the use of PPE in PT Wika Beton Boyoali construction workers.18
Meanwhile, the lack of knowledge of the print manager or director can also cause dissonance
in which managers or employers do not make any regulations for wearing PPE and do not provide
adequate knowledge to printing employees about the dangers of benzene exposure and the
importance of wearing PPE. This is in accordance with PERMENAKERTRANS Regulation No.
08/MEN/VII/2010 Article 5, which states that entrepreneurs or managers are obliged to announce
in writing and put up signs regarding the mandatory use of PPE in the workplace. Employers and
managers are also required to equip employees who work in printing companies with knowledge of
the dangers of chemical exposure and the importance of wearing PPE.19
3. Attitudes of Workers in Wearing PPE
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 19
The attitude of workers in wearing PPE was measured through in-depth interviews and
observations for a week. Based on the results of in-depth interviews with seven key informants,
two of the seven key informants never wore masks at all and the other five wore masks at certain
times, namely when they were sick and when the smell of ink was very strong. In addition, there
are no printing machine operators who wear masks regularly because they feel uncomfortable and
hot when wearing masks, operators also find it difficult to communicate while working while
wearing masks, and some printing machine operators say they do not know how to wear the correct
surgical mask because not sure which side of the mask is outside inside when wearing it. This
result is not in accordance with the research of Maesaroh & Nurtjahjanti which shows that there is
a positive relationship between attitudes and the use of PPE, this positive relationship can result in
more frequent use of PPE.20
Likewise with Prasetyo's research which shows that there is a positive
attitude towards the majority of PT. Pura Barutama Kudus with the use of PPE and resulting in
compliance with the use of PPE.21
From the discrepancies of the observation results with previous
research, it can be concluded that there is no significant relationship between attitudes and the use
of PPE in X and Y Printing Company.
Changing the attitude of employees of X and Y Printing Company can be through Behavior
Change Strategies by WHO, behavior change can occur through; natural change, planned change,
and willingness to change. Meanwhile, to change the attitude or behavior itself can be done in three
ways; use force (enforcement), rule of law and law, and education.22
Enforcement can change behavior through bullying, but change may not last long because
individuals who must change must realize the benefits of changing their own behavior. Using
regulations and laws can be used by making written regulations regarding PPE at X and Y Printing
Company which are used as references. The last way to change someone's behavior is through
effective education with the discussion method. The existence of discussions between managers
and printing workers or between workers about the risks of benzene exposure and the use of PPE
can change the behavior of workers in wearing PPE while working. To realize this, workers and
managers as well as employers must create a good working atmosphere and work relations so that
discussions about the use of PPE at work can run well. At the same time, to support education as a
method of changing attitudes, it is also important to establish legal regulations so that they can
become the basis for strengthening attitude change with education.
4. Regulations for the Use of PPE in the Workplace
In Siregar's research, shows that the majority of respondents who are printing employees do
not use PPE This is due to the discomfort of the PPE used, and the absence of a system or
procedure in the printing industry that requires workers to use PPE while working.23
This
phenomenon is almost the same as the results of in-depth interviews with X printing machine
operators and printing machine operators Y Printing Company, where operators claim to be
uncomfortable when wearing masks while working and the absence of definite rules or regulations
regarding the use of PPE in printing causing supervision and procedures wearing PPE is loose.
The director and manager of X and Y Printing Company do not have a fixed regulation
regarding the use of PPE in printing. In accordance with the PERMENAKERTRANS Regulation
No. 08/MEN/VII/2010 Article 5, entrepreneurs or managers of a company are required to announce
in writing and put up signs regarding the mandatory use of PPE in the workplace.19
The application of PPE is the last risk control step that can be taken based on the risk
management hierarchy by the Health and Safety Executive by the Health and Safety Executive.
Before taking the step of providing PPE, X Printing Company has provided administrative
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 20
management steps where the printing company provides sterile milk to minimize the impact of
exposure to toluene. Although sterile milk has been shown to minimize the effects of poisoning,
there are no studies that can confirm that sterile milk can reduce the effects of benzene exposure
and its derivatives. X Printing Company also does not comply with the Medical Guidelines for
Toluene by the Agency for Toxic Substances and Disease Registry which states that there is no
specific medical treatment to treat exposure to toluene or toluene poisoning.11
If X and Y Printing Company apply a regulation regarding the use of PPE in the workplace,
then the entrepreneur or manager is obliged to announce in writing to all employees. Implementing
regulations and also providing knowledge about the risks of chemical hazards, especially exposure
to benzene in printing, can change the behavior of workers to comply with wearing PPE while
working.
5. Availability of PPE
X and Y Printing Company have provided masks for printing machine operators and other
employees. This is in accordance with PERMENAKERTRANS Regulation Number
08/MEN/VII/2010 article 2 which states: 'employers are obliged to provide PPE for
workers/laborers in providing PPE such as gloves, aprons, and shoes, as well as other types of
masks or respirators for workers. Provision of gloves, aprons, and shoes is important because
printing workers, especially printing machine operators, are at risk of being exposed to ink and
alcohol through the skin.19
However, during the 7-day observation conducted by the researcher, it
was shown that the frequency of using PPE was still very low at X and Y Printing Company even
though PPE masks were provided. This shows that there is no significant relationship between the
availability of PPE and compliance with the use of PPE. The results of this observation are
consistent with Soendoro's research, in the results of Soendoro's research, compliance with the use
of PPE in printing does not have a strong correlation with the availability of PPE.24
This is due to
several reasons such as the discomfort of PPE and the lack of PPE alternatives provided, which are
also in line with the results of in-depth interviews at X and Y Printing Company where employees
do not wear PPE due to the discomfort of PPE.
The types of masks provided for X Printing Company employees are cloth masks and the
types of masks provided for Y Printing Company employees are surgical masks. The reason why X
Printing Company provides motorcycle masks for its employees is that the availability of surgical
masks in pharmacies can be limited at any time.
Rules for wearing masks according to WHO, disposable masks such as surgical masks are
used only once before being thrown away. Meanwhile, the effectiveness of cloth masks has not
been proven to protect the wearer from exposure to viruses, bacteria, or chemicals. Surgical masks,
also known as surgical masks, do not have the perfect ability to cover the nose and mouth because
they have gaps on all four sides of the mask when worn. Wearing a procedure mask is not the right
step to reduce the risk of exposure to dust and chemical gases because procedure masks are not
certified as good respirators by the National for Occupational Safety and Health (NIOSH) and the
European Committee for Standardization (ECS).25
In order to reduce the risk impact of benzene exposure, employees of X and Y Printing
Company need a tight-fitting respirator that can cover half the face. An example of a respirator that
is easily available and used is the N95 respirator. In addition to masks, X and Y Printing Company
need to provide protective equipment for feet, hands, and body in accordance with the regulations
of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Regulation of the
Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 21
Per.08/MEN/VII/2010 concerning Personal protective equipment. The recommended foot, hand
and body protection can be in the form of footwear or shoes, gloves and aprons to prevent skin
contact with solvents and inks while working. Foot protection, gloves, and aprons are needed
because ink and solvent contact with the skin can cause irritation and allergies, even blistering if
exposed to too long and frequently as research by Agbenorku, on the occupational risks of workers
in a printing press in Ghana, India, shows that dermatitis and several other skin diseases are among
the main diseases suffered by workers in printing due to contact with inks, solvents, and some other
chemicals while working.26
6. Supervision from Managers or Entrepreneurs
Based on the results of observations during the week conducted by researchers, the
supervision while working in a printing shop is still lacking because entrepreneurs do not have
regulations and do not apply regulations regarding the use of PPE. This is also supported by the
lack of supervision from managers. Employers are also rarely shown directly by employees in the
print room. For X Printing Company, it is lax to supervise busy owners or managers, while for X
Printing Company, it is lax to supervise because the printer has CCTV for employees to work with.
Managers who are in the printing press more often remind printing machine operators to wear PPE,
but the implementation of PPE usage is still not optimal because printing machine operators feel
hot and uncomfortable when wearing masks. The absence of regulations resulting in no sanctions
or sanctions for those who do not wear PPE while working. The results of this study are not in
accordance with the research of Jatmiko et al which states that there is a significant relationship
between supervision and the use of PPE on construction workers. The results of research by Lobis
& Ariyanto also show that there is a significant influence between the supervision and use of PPE
at PT Jamu Air Mancur Palu, this result is not consistent with the results of observations at X and Y
Printing Company which even though the manager has destroyed the work process at printing, did
not show an increase in the frequency of using PPE.27
Control or supervising is a function in functional management that must be carried out by
every leader of all units/work units for the implementation of work or employees who carry out in
accordance with their respective main duties. Thus, supervision by leaders, especially those who
have built-in control, is a managerial activity carried out with the intention of avoiding
irregularities in carrying out work. A deviation or error occurs or not during work performance
depending on the ability and skill level of the employee. Employees who always receive direction
or guidance from their superiors tend to make fewer mistakes or deviations than employees who do
not receive guidance from their superiors.
CONCLUSION
Based on the results of interviews with informants, as many as 7 informants experienced
mild symptoms of exposure to toluene such as nausea and dizziness, which correspond to acute
symptoms caused by exposure to benzene and its derivatives. The main source of exposure to
toluene is inks which contain synthetic dyes derived from aromatic hydrocarbons such as benzene
and toluene which are benzene derivatives. The knowledge of printing machine operators and
offset printing managers in the city of Palembang regarding the impact of toluene exposure and the
use of PPE is still lacking, and with supervision and no permanent regulations on the use of PPE,
the application of the use of PPE in offset printing within 8 working hours per day is still lacking.
To improve this condition, Manager and Director of X and Y Printing Company must provides
knowledge about the dangers of toluene exposure in printing and the function along the benefit of
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 22
using PPE to printing employees, especially printing machine operators. In addition, the printing
company must provides N95 respirators or other standard respirators as well as other PPE such as
aprons, shoes and gloves for the employees' PPE in the printing shop.
REFERENCES
1. Sumarna DP, Naiem MF, Russeng SS. Determinan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Pada Karyawan Percetakan Di Kota Makassar. 2013;1–15.
2. Department HOS and HBL. Chemical Safety in Printing Industry. 2017;
3. Muchtar H, Anova IT, Yeni G. Pengaruh Kecepatan Pengadukan Dan Kehalusan Gambir
Serta Variasi Komposisi Terhadap Beberapa Sifat Fisika Dalam Pembuatan Tinta Cetak.
2015;131–9.
4. Setiyono. Teknologi Pengelolaan Limbah Industri Percetakan. 2002;5.
5. SNI. Kategori Bahan Kimia Karsinogenik untuk Manusia. 2005;
6. Fatmawati NS, Hermana J, Slamet A, Lingkungan T, Teknik F, Teknologi I, et al. Optimasi
Kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah Industri Penyamakan Kulit Magetan. 2016;5(2).
7. Notoatmodjo S. Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan. 2003;
8. Heryana A. Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif.
2018;(December).
9. Novick RM, Keenan JJ, Gross SA, Paustenbach DJ. An Analysis of Historical Exposures of
Pressmen to Airborne Benzene ( 1938 – 2006 ). 2013;57(6):705–16.
10. Ishikawa W, Hachioji. Actinic Ray Curable Composition, Actinic Ray Curable Ink, Image
Formation Method Employing It, And Ink-Jet Recordingapparatus. 2009;2(12).
11. Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Medical Management Guidelines for
Toluene. 2014;
12. Faisal HD, Susanto AD. Peran Masker/Respirator dalam Pencegahan Dampak Kesehatan
Paru Akibat Polusi Udara. 2017;3(1).
13. WHO. Exposure To Benzene : A Major Public Health Concern. 2010;
14. Nikmah WI, D YH. Hubungan Antara Paparan Benzena Dengan Profil Darah Pada Pekerja
Di Industri. 2016;4:213–20.
15. Australian Centre for Human Health Risk Assessment. Enviroment Health Risk
Assessment. 2012;
16. Febriantika D, Sulistiyani, Budiyono. Analisis Risisko Kesehatan Pajanan Benzena Di
Industri Percetakan X Kota Semarang. 2017. 2017;5.
17. Hidalgo-baz M, Martos-partal M, González-benito Ó. Attitudes vs . Purchase Behaviors as
Experienced Dissonance : The Roles of Knowledge and Consumer Orientations in Organic
Market. 2017;8(February):1–8.
18. Jatmiko F, Setiyawan H, Atmojo TB. Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Dan
Pengawasan Terhadap Perilaku Pemakaian Apd Pada Pekerja. 2017;2(1).
19. PERMENAKERTRANS. Peraturan No. 08/MEN/VII/2010 pasal 2.
20. Maesaroh S, Nurtjahjanti H. Hubungan Antara Sikap Terhadap Alat Pelindung Diri (APD)
Dengan Komitmen Organisasi Pada Karyawan Bagian Ohs Pt. Coca-Cola Bottling
Indonesia Semarang Plant. 2013;
21. Prasetyo E. Pengaruh Pengetahuan , Sikap , Dan Ketersediaan Alat Pelindung Diri ( Apd )
Terhadap Kepatuhan Dalam Menggunakan Apd Di Unit Coating Pt . Pura Barutama Kudus.
2015;
22. WHO. Guidelines for Developing Behavioural Change Interventions in the Context of
Avian Influenza. 20068;
23. Siregar AF, Ashar T, Nurmaini. Paparan benzena di udara ambien dan kadar trans- trans
muconic acid urin pada pekerja industri percetakan di kota Medan. 2019;35(3):107–12.
24. Soendoro A. Hubungan Pengetahuan, Sikap, Ketersediaan APD Dengan Kepatuhan
Pemakaian APD Pekerja Bagian Weaving PT Iskandar Indah Printing Textile. 2016;
25. Kartikasari D, Nurjazuli, Rahardjo M. Analisis Risiko Kesehatan Pajanan Benzene Pada
Pekerja Di Bagian Laboratorium Industri Pengolahan Minyak Bumi. 2016;4:892–9.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 23
26. Agbenorku P, Agbenorku M. A Prospective Study of Diseases Associated With Workers in
the Printing Industry in a City of Ghana A Prospective Study of Diseases Associated With
Workers in the Printing Industry in a City of Ghana. 2012;(June 2014).
27. Lobis YB, Ariyanto D. Pengaruh Pengawasan Terhadap Kepatuhan Penggunaan Alat
Pelindung Diri Di Pt Jamu Air Mancur Palur. 2020;8(1):31–5.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 24
PERBANDINGAN SANITASI SEKOLAH DASAR BERDASARKAN AKREDITASI
SEKOLAH: STUDI KUALITATIF
Russy Rakhmalia, Yustini Ardillah*
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya *Corresponding Email: [email protected]
COMPARISON OF ELEMENTARY SCHOOL SANITATION: A QUALITATIVE STUDY
ABSTRACT
Sanitation is a basic need that must be met in public places such as schools. Every school should have
sanitation standards that must be met. The aim of this study was to compare school sanitation based on
school accreditation.This study compared two schools based on school accreditation, two schools were
recruited to be the subjects in this study with a total of 11 informants consisting of principals, teachers and
students from each school. The data analysis used is content analysis. Triangulation of sources, methods and
data was carried out to test the validity. Schools that have good accrditation meet the criteria for school
sanitation with good scores School sanitation should be a priority for all schools regardless of the value of
accreditation
Keyword: School Sanitation, Qualitative, Accreditation
ABSTRAK
Sanitasi merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi di tempat – tempat umum seperti sekolah. Setiap
sekolah seharusnya mempunyai standar sanitasi yang wajib dipenuhi. Tujuan penelitian ini adalah untuk
membandingkan sanitasi sekolah berdasarkan akreditasi sekolah. Penelitian ini membandingkan dua sekolah
berdasarkan akreditasi sekolah, dua sekolah direkrut untuk menjadi subjek dalam penelian ini dengan total 11
informan yang terdiri dari, kepala sekolah, guru dan siswa dari masing – masing sekolah. Analisis data yang
digunakan adalah content analysis. Triangulasi sumber, metode dan data dilakukan untuk menguji validitas.
Sekolah yang memiliki akrditasi yang baik memenuhi kriteria sanitasi sekolah dengan nilai yang baik.
Sanitasi sekolah seharusnya menjadi prioritas bagi seluruh sekolah tanpa membedakan nilai akreditasi
Kata Kunci: Sanitasi Sekolah, Kulaitatif, Akreditasi
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 25
PENDAHULUAN
Sanitasi Sekolah menjadi bagian penting dalam pencapaian SDGs, semua sekolah di
Indonesia ditargetkan mencapai indikator SDGs di tahun 2030.1 Sanitasi Sekolah yang dimaksud
meliputi penyediaan air bersih, jamban, sarana saluran pembuangan air limbah (SPAL), dan sarana
pembuangan sampah yang harus dimiliki sekolah sesuai peraturan pemerintah.2 Jenjang Sekolah
Dasar (SD) merupakan jenjang pendidikan dengan kondisi sanitasi sekolah yang terburuk
dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya, dengan memiliki indeks sanitasi sekolah sebesar
53,75%.3
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Santi and al Bahiij 4 menemukan bahwa Banyak
sekolah dasar yang tidak memenuhi syarat, dari konstruksi bangunan, jamban, air bersih,
pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air limbah (SPAL). Penelitian lainnya juga
menemukan bahwa mengatakan 80% sekolah dasar di Surabaya Barat kondisi fisik sekolahnya
tidak sesuai, 60% toilet sekolah dasar Surabaya Barat dan 73% toilet SD Surabaya Utara tidak
memisahkan toilet antara laki-laki dan perempuan. Tempat sampah yang tidak dilengkapi dengan
tutup sebesar 47% di sekolah dasar Surabaya Barat sedangkan di sekolah dasar Surabaya Utara
sebesar 50%.5
Ketidaklayakan sanitasi akan menjadi resiko untuk berkembangnya penyakit menular.6
Sementara Sekolah dasar merupakan tempat – tempat umum yang interaksi intensif anak – anak
pada lingkungan terjadi.7 Akreditasi Sekolah menjadi pilihan bagi masyarakat untuk mendaftarkan
anak – anak mereka pada sekolah tertentu, sehingga menjadi nilai jula bagi sebuah sekolah.
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan Kelayakan sanitasi berdasarkan akreditasi yang
dimiliki.
METODE
Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif observasional dengan pendekatan
kualitatif. Sampel penelitian ini adalah SD Negeri 222 dengan akreditasi B dan SD Negeri 234
dengan akreditasi A. Informan penelitian ini berjumlah 11 orang, terdiri dari 5 orang informan
kunci dan 6 orang informan biasa. Teknik sampling yang digunakan adalah non probability
sampling yaitu purposive sampling. pengumpulan data menggnakan data primer yaitu dilakukan
dengan cara wawancara mendalam, observasi, lembar checklist dan dokumentasi.
HASIL PENELITIAN
Penelitian ini mengenai fasilitas sanitasi lingkungan ini terdiri dari sarana sumber air bersih,
sarana jamban, sarana saluran pembuangan air limbah (SPAL), sarana tempat pembuangan sampah
dan sumber pembiayaan.
Sarana Sumber Air Bersih
Hasil observasi dengan lembar checklist terhadap sarana sumber air bersih dapat dilihat pada
Tabel 1.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 26
Tabel 1. Hasil Observasi Sarana Sumber Air Bersih
Komponen yang dinilai SDN 222 SDN 234
MS TMS MS TMS
Tersedia sumber air bersih √ - √ -
Jenis sumber air bersih:
PDAM
Sumur gali
Sumur pompa tangan
Lain-lain
√
-
√
-
Memiliki jarak >10 meter dari septic tank atau sumber pencemar √ - √ -
Kondisi fisik air: Tidak berbau
√
-
√ -
Tidak berasa √ - √ -
Tidak berwarna √ - √ -
Air bersih selalu ada/tersedia - √ √ -
Kecukupan sumber air bersih - √ √ -
Dari hasil penelitian sarana sumber air bersih yang telah ditetapkan Kepmenkes No. 1429
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah, kedua sekolah
tersedia sumber air bersih dengan jenis sumber air bersih yaitu berasal dari air PDAM. Lokasi
sumber air bersih telah memenuhi syarat yaitu berlokasi dengan jarak >10 meter dari sumber
pencemar. Untuk kualitas sumber air bersih dari kondisi fisiknya telah memenuhi syarat yaitu tidak
berbau, tidak berasa dan tidak berwarna. Selanjutnya mengenai tersedia (kontinuitas) dan
kecukupan (kuantitas) sumber air bersih hanya ada 1 sekolah yang memenuhi syarat yaitu SD
Negeri 234 Palembang.
Sarana Jamban
Hasil observasi dengan lembar checklist terhadap sarana jamban dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Sarana Jamban
Komponen yang dinilai SD N 222 SD N 234
MS TMS MS TMS
Tersedia jamban √ - √ -
Jenis jamban:
Jamban leher angsa cemplung
Jamban cemplung
Jamban gantung
Lain-lain
√
-
√
-
Tersedia jamban terpisah antara laki-laki dan perempuan √ - √ -
Tersedia jamban yang cukup (1 jamban/25 siswi dan 1 jamban/40 siswa) atau (1 jamban/50 siswi dan 1 jamban/60
siswa)
- √ - √
Tersedia air bersih di setiap jamban - √ √ -
Memiliki dinding, lantai dan atap pelindung yang kuat √ - √ -
Cukup penerangan √ - √ -
Terdapat ventilasi √ - √ - Jarak jamban dengan sumber air bersih >10meter √ - √ -
Ada septic tank √ - √ -
Jarak septic tank dengan sumber air bersih >10meter √ - √ -
Septic tank memiliki saluran tertutup √ - √ - Tidak ada jentik nyamuk dalam bak penampung air √ - √ -
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 27
Tidak ada lalat atau kecoa dalam jamban √ - √ - Tidak ada genangan air di lantai √ - √ -
Tidak berbau √ - √ -
Perlengkapan pada jamban:
Gayung
Gantungan pakaian
Sabun
Alat pembersih
√
√
√
√
√ √
√
√
Dari hasil observasi yang dilakukan, sarana jamban yang memenuhi syarat berdasarkan
Kepmenkes No. 1429 Tahun 2006 pada SD Negeri 222 Palembang dan SD Negeri 234 Palembang
yaitu jenis jamban leher angsa dengan terpisahnya jamban untuk laki- laki dan perempuan,
memiliki dinding, lantai dan atap pelindung yang kuat, cukup penerangan, terdapat ventilasi, jarak
jamban dengan sumber air bersih >10meter, ada septic tank, tidak ada jentik nyamuk dalam bak
penampung air, tidak ada lalat atau kecoa dalam jamban, tidak ada genangan air di lantai,
perlengkapan yang ada di dalam jamban gayung dan alat pembersih.
Sarana Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)
Hasil observasi dengan lembar checklist terhadap sarana Saluran Pembuangan Air Limbah
(SPAL) dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Sarana Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)
Komponen yang dinilai SD N 222 SD N 234
MS TMS MS TMS
Tersedia SPAL √ - √ -
Jenis SPAL: SPAL tertutup
SPAL tidak tertutup
-
√
- √
Saluran terpisah dengan saluran penuntasan air hujan - √ √
Bebas dari sarang nyamuk dan tikus - √ - √
Tidak menimbulkan bau - √ √ -
SPAL kedap air √ - √ -
SPAL mengalir dengan lancar - √ √ -
Dari hasil tabel di atas diketahui bahwa sarana SPAL pada SD Negeri 222 Palembang yang
memenuhi syarat yaitu tersedia SPAL dan kedap air. Sedangkan sarana SPAL pada SD Negeri 234
Palembang yang memenuhi syarat yaitu tersedia SPAL, saluran terpisah dengan saluran penuntasan
air hujan, tidak menimbulkan bau, kedap air dan mengalir dengan lancar.
Sarana Tempat Pembuangan Sampah
Hasil observasi dengan lembar checklist terhadap sarana jamban dapat dilihat pada Tabel 4.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 28
Tabel 4.Sarana Tempat Pembuangan Sampah
Komponen yang dinilai SD N 222 SD N 234
MS TMS MS TMS
Tersedia tempat sampah √ - √ -
Dibersihkan setiap 24 jam sekali √ - √ -
Tempat sampah tidak bocor √ - √ -
Tempat sampah mudah dibersihkan √ - √ - Tempat sampah tertutup √ - √ -
Tempat sampah sesuai jenis √ - √ -
Tempat penampungan sampah sementara berjarak >10 meter dari ruang
kelas - √ - √
Pemisahan sampah organik dan anorganik √ - √ -
Sampah diangkut petugas √ - √ -
Pengolahan sampah:
Landfill
Composting
Dumping
Recycling
Salvaging
Lain-lain
√
-
-
- -
-
√
√
-
-
-
-
Dari hasil tabel di atas diketahui bahwa sarana tempat pembuangan sampah pada SD Negeri
222 Palembang dan SD Negeri 234 Palembang yang memenuhi syarat yaitu tersedia tempat
sampah, dibersihkan setiap 24 jam sekali, tempat sampah tidak bocor, mudah dibersihkan, tertutup,
sampah sesuai jenis, tempat penampungan sampah sementara berjarak >10 meter dari ruang kelas,
pemisahan sampah organik dan anorganik, dan sampah diangkut petugas. Pengolahan sampah pada
SD Negeri 222 Palembang hanya dumping sedangkan Pengolahan sampah pada SD Negeri 234
Palembang yaitu dumping dan recycling.
Pembiayaan
Dilakukannya wawancara kepada informan kunci terkait sumber pembiayaan mengenai
fasilitas sanitasi lingkungan pada SD Negeri 222 Palembang dan SD Negeri 234 Palembang. Dari
hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa sumber pembiayaan pada kedua sekolah yaitu
berasal dari Pemerintah berupa dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang didapatkan setiap
triwulan atau 1 kali setiap 3 bulannya.
Pembagian dana BOS untuk barang dan jasa di digunakan untuk memberikan gaji kepada
petugas kebersihan sekolah, membayar sarana sumber air bersih yaitu air PDAM, untuk
memberikan gaji kepada petugas Dinas Kebersihan Kota yang mengangkut sampah dari sekolah,
sedangkan dana untuk membeli keperluan peralatan seperti sikat, tempat pembuangan sampah
berupa kotak sampah, dan juga untuk pemeliharaan fasilitas sarana sanitasi tersebut tidak bisa
dipastikan berapa jumlah dana yang dibutuhkan, dikarenakan pergantian peralatan dilakukan jika
peralatan sebelumnya mengalami kerusakan.
PEMBAHASAN Sarana Sumber Air Bersih
Dari hasil penelitian, SD Negeri 222 Palembang dan SD Negeri 234 Palembang sudah
memiliki sarana sumber air bersih. Kedua sekolah memiliki jenis sumber air bersih yaitu air
PDAM. Semua kegiatan yang dilakukan di lingkungan sekolah menggunakan air PDAM. Kondisi
air bersih secara fisik yang disediakan dan lokasi sumber air bersih berjarak >10 meter dengan
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 29
sumber pencemar atau septic tank semuanya sudah memenuhi syarat. Air yang digunakan tidak
berwarna, tidak berasa dan juga tidak berbau.
Sumber air bersih harus berjarak minimal 10 meter dari septic tank. Hal ini agar tidak terjadi
pencemaran oleh tinja yang berada di septic tank. Tinja merupakan media penularan kecacingan
selain tanah. Apabila jarak antara sumber air bersih dan septic tank tersebut kurang dari 10 meter
maka risiko pencemaran telur cacing melalui tinja pada air jauh lebih besar.8
Air bersih pada SD Negeri 222 Palembang tidak selalu tersedia dan kecukupan jumlah air
tersebut belum memenuhi syarat untuk keperluan warga sekolah setiap harinya. Penelitian
Shrestha, Sharma 9 mengatakan, penyediaan air bersih hendaknya memperhatikan sumber, kualitas
dan kuantitasnya. Sumber air bersih merupakan pemasok air bersih oleh karena itu perlu dan harus
diupayakan menjaga keberadaan dan keberlanjutannya. Sedangkan kualitas merupakan hal yang
penting bagi kesehatan dan kuantitas penting bagi pencukupan jumlah pasokan air bersih.
Kepmenkes No. 1429 Tahun 2006 mengatur bahwa sumber air bersih di skeolah harus tersedia
dalam jumlah yang cukup untuk setiap harinya. Kualitas air yang disediakan juga harus memenuhi
syarat dan jarak antara sumber air bersih dengan sumber pencemar atau septic tank >10 meter.
Sarana Jamban
Dari hasil penelitian diketahui semua jamban yang ada di SD Negeri 222 Palembang dan SD
Negeri 234 Palembang berupa jamban leher angsa. Diketahui juga bahwa jamban di SD Negeri 222
Palembang tersedia sebanyak 9 unit. Hanya 5 jamban saja yang berfungsi. 5 jamban tersebut yaitu
1 jamban guru, 2 jamban siswa dan 2 jamban siswi dengan jumlah siswa 337 anak dan siswi 300
anak. Dari segi ketersediaan jamban, baik itu berdasarkan Kepmenkes No. 1429/MENKES/SK/XII,
jumlah jamban tersebut belum cukup untuk memenuhi rasio yang ditetapkan oleh menteri
kesehatan yaitu 1:40 untuk siswa, dan 1:25 untuk siswi maupun Permendiknas RI No. 24 Tahun
2007 yaitu dengan rasio 1:60 untuk siswa dan 1:50 untuk siswi.
Selanjutnya, jumlah jamban yang dimiliki SD Negeri 234 Palembang yaitu 11 jamban,
dimana 2 untuk guru, 1 untuk kepala sekolah, 4 untuk siswa dan 4 untuk siswi, dengan jumlah
siswa 438 anak dan siswi 405 anak. Dari segi ketersediaan jamban, baik itu berdasarkan
Kepmenkes No. 1429/MENKES/SK/XII, jumlah jamban tersebut belum cukup untuk memenuhi
rasio yang ditetapkan oleh menteri kesehatan yaitu 1:40 untuk siswa, dan 1:25 untuk siswi maupun
Permendiknas RI No. 24 Tahun 2007 yaitu dengan rasio 1:60 untuk siswa dan 1:50 untuk siswi.
Semua jamban di kedua sekolah dalam kondisi memiliki dinding, lantai dan atap pelindung
yang kuat, cukup penerangan, terdapat ventilasi di setiap jamban, lokasi jamban >10 meter dengan
sumber air bersih, tersedia septic tank dalam keadaan tertutup, dan jarak septic tank >10 meter
dengan sumber air bersih, tidak ada jentik nyamuk dalam bak penampung air, tidak terdapat lalat
atau kecoa dalam jamban, tidak ada genangan air dilantai dan tidak berbau.
Perlengkapan di dalam jamban yang dimiliki SD Negeri 222 Palembang yaitu gayung dan
alat pembersih sedangkan perlengkapan di dalam jamban yang dimiliki SD Negeri 234 Palembang
yaitu gayung, gantungan pakaian dan alat pembersih. Kedua sekolah tidak memilik sabun di dalam
jamban tersebut. Yang belum tersedia dengan baik adalah ketersediaan sabun untuk setiap jamban.
Ketersediaan air bersih dalam jamban di SD Negeri 222 Palembang masih kurang baik, hal ini
karena ditemukannya saat dilakukan observasi ke lapangan terdapat bak-bak penampungan air
dalam jamban yang tidak terisi atau kosong.
Ketersediaan air bersih yang memenuhi syarat di lingkungan sekolah sangatlah penting
sebagai salah satu upaya pencegahan infeksi kecacingan pada murid di sekolah. Penularan cacing
dapat terjadi melalui air dan makanan yang terkontaminasi oleh telur dan larva cacing.10
Penggunaan jamban yang tidak memenuhi syarat menyebabkan kontaminasi bakteri akibat tinja
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 30
yang tidak di proses dengan benar yang mengakibatkan tinja mencemari lingkungan dan bakteri
dalam kandungan tinja masuk ke tubuh manusia dan menyebabkan beberapa penyakit.11
Sarana Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)
Dari hasil penelitian yang dilakukan pada SD Negeri 222 Palembang dan SD Negeri 234
Palembang diketahui bahwa kedua sekolah telah memiliki SPAL berupa selokan yang terletak di
dalam dan di luar sekolah. SPAL yang ada pada kedua sekolah dapat dikatakan masih dalam
kondisi yang kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari SPAL yang belum dilengkapi penutup. Kondisi
SPAL kedap air. SPAL kedua sekolah tidak terbebas dari sarang nyamuk dan tikus. SPAL di SD
Negeri 234 Palembang, keadaan SPAL tidak menimbulkan bau dan juga mengalir dengan lancar.
Sedangkan SPAL di SD Negeri 222 Palembang dalam keadaan baud an juga tidak mengalir dengan
lancar. Hal ini disebabkan karena terjadi penyumbatan saluran oleh sampah disebabkan petugas
kebersihan sekolah yang tidak melakukan pembersihan secara rutin ataupun apabila terjadi
penyumbatan saluran sehingga pembuangan air limbah tiak terganggu. Sampah-sampah yang ada
di dalam SPAL dikarenakan warga sekolah itu sendiri ataupun karena pedagang yang membuang
sampah ke dalam saluran. Sampah ini juga disebabkan karena tidak ada penutup saluran. SPAL
pada SD Negeri 222 Palembang juga tidak terpisah dengan penuntasan air hujan, jadi air limbah
dan air hujan berada dalam saluran yang sama.
Persyaratan yang diatur dalam Kepmenkes No. 1429 Tahun 2006 menyatakan SPAL pada
sekolah harus terpisah dengan saluran penuntasan air hujan, terbuat dari bahan kedap air dan
tertutup dengan kisi yang terbuat dari logam, keberadaan SPAL tidak mencemari lingkungan dan
airnya mengalir dengan lancar. Pembuangan air limbah yang tidak dikelola dengan baik dan
memenuhi syarat kesehatan dapat dijadikan sebagai salah satu tempat perindukan vektor penyakit
sehingga menjadi sumber penularan berbagai penyakit, saluran pembuangan air limbah yang
terbuka juga dapat menimbulkan bau serta menjadi sarana perkembangbiakkan vektor penyebar
penyakit seperti tikus. Limbah-limbah yang tidak dikelola akan mencemari lingkungan, dan itu
tentu saja akan menimbulkan akibat yang buruk bagi lingkungan cepat atau lambat serta dapat
menggangu kesehatan siswa.12
Sarana Tempat Pembuangan Sampah
Dari hasil penelitian kedua sekolah sudah memiliki tempat pembuangan sampah berupa
kotak sampah yang tersedia di setiap depan ruang kelas. Kotak sampah tersebut dibersihkan setiap
24 jam sekali sama petugas kebersihan di sekolah. Lokasi kotak sampah di kedua sekolah belum
memenuhi syarat yaitu >10 meter dari ruang kelas. Lokasi kotak sampah berada tepat di depan
ataupun di pintu masuk ke dalam ruang kelas.
Kotak sampah di SD Negeri 222 Palembang hanya mempunyai 1 kotak sampah yang
memenuhi syarat, yaitu terletak di depan ruang guru. Sedangkan kotak sampah yang ada di depan
ruang kelas semuanya tidak memenuhi syarat. Kondisi tempat sampah itu sendiri tidak memiliki
tutup, tempat sampahnya dalam keadaan bocor, tidak ada pemisahan organik dan anorganik,
semuanya dimasukkan dalam satu tempat kotak sampah yang sama. Keadaan kotak sampah yang
bocor tersebut menjadikannya sampah berserakan di depan ruang kelas. Kesadaran dalam hal
perawatan kotak sampah dan membersihkan sampah untuk SD Negeri 222 Palembang masih sangat
kurang. Tidak dilakukannya pergantian terhadap kotak sampah yang telah rusak.
Sarana pembuangan sampah di sekolah sangatlah penting untuk menampung sampah-
sampah agar tidak berserakan. Sampah yang berserakan dapat menjadi tempat berkembangbiaknya
bibit penyakit untuk siswa yang ada di sekolah. Oleh karena itu, diperlukannya tempat
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 31
penampungan sampah untuk setiap ruang kelas yang dilengkapi dengan tutup agar aroma yang
tidak sedap dari sampah tidak menganggu kenyamanan belajar siswa.13
Keadaan kondisi tempat sampah di SD Negeri 222 Palembang sangat berbeda sekali dengan
kondisi tempat sampah yang ada pada SD Negeri 234 Palembang. Kondisi kotak sampah di SD
Negeri 234 Palembang seara keseluruhan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya
tempat sampah yang sudah berdasarkan jenis sampahnya. Terdapat 3 jenis kotak sampah di sekolah
tersebut, yaitu sampah oragnik, sampah anorganik dan sampah B3. Kondisi tempat sampahnya
dalam keadaan tertutup, tidak bocor, mudah untuk dibersihkan. Dilakukannya pemilahan sampah
seperti botol plastik untuk dibuat prakarya sedangkan untuk sampah lainnya dibuang untuk
diangkut sama petugas Dinas Kebersihan Kota. Dilakukannya pemilahan sampah botol plastik
untuk dijadikan sebuah prakarya dengan tujuan untuk mengurangi sampah plastik dengn cara
memanfaatkannya kembali. Upaya pengelolaan sampah yang telah dilakukan SD Negeri 222
Palembang dan SD Negeri 234 Palembang hanya sebatas pewadahan dan pengumpulan, sementara
untuk pengangkutan dan pembuangan akhir dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota.
UU No. 18 Tahun 2008 menyatakan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah wajib
mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berawawasan lingkungan. Pengurangan
sampah ini melikputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran sampah, dan pemanfaatan
kembali sampah. Sementara itu untuk kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan,
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Dalam Kepmenkes No.
1429/MENKES/SK/XII diatur bahwa pada setiap ruangan kelas harus tersedia tempat sampah yang
dilengkapi dengan tutup. Setiap sekolah juga harus memiliki tempat pembuangan sampah
sementara. Adapun syarat tempat sampah dan tempat pembuangan sampah sementara yang baik
adalah terbuat dari bahan yang kedap air, mudah dibersihkan, dan tertutup. Lokasi tempat
pembuangan sampah sementara juga harus mudah dijangkau oleh petugas pengangkut sampah dan
berada pada minimal 10 meter dari ruangan kelas.
Sumber Pembiayaan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di dua sekolah yaitu SD Negeri 222 Palembang dan
SD Negeri 234 Palembang, diketahui bahwa sumber pembiayaan yang didapatkan yaitu berasal
dari pemerintah berupa dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Dana tersebut didapatkan setiap
triwulan atau 1 kali untuk setiap 3 bulannya dengan total yaitu 4 (empat) kali pencairan dana yang
didapatkan di kedua sekolah tersebut.
Dalam perealisasiannya baik itu SD Negeri 222 Palembang dan SD Negeri 234 Palembang
digunakan untuk menggaji petugas kebersihkan sekolah, membayar petugas Dinas Kebersihan
Kota, untuk membayar pembiayaan sumber air yang berasal dari air PDAM, dan untuk membeli
peralatan terkait fasilitas sanitasi lingkungan di sekolah seperti alat sikat jamban/wc, cairan
pembersih untuk jamban, perlengkapan di dalam jamban berupa sabun, dan juga pembeliaan
tempat pembuangan sampah berupa kotak sampah untuk setiap kelasnya. Akan tetapi dalam
perealisasiannya, baik itu SD Negeri 222 Palembang ataupun SD Negeri 234 Palembang tidak
melakukan pergantian terhadap peralatan secara rutin, peralatan hanya dilakukan pergantian jika
terjadi kerusakan terhadap peralatan tersebut.
Dana BOS didapatkan sekolah untuk meningkatkan kualitas sekolahnya dalam hal perawatan
dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Biaya pendidikan merupakan
salah satu faktor penting dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah guna memberikan
fasilitas baik itu sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini seharusnya dilakukan dengan cara
melakukan pergantian peralatan secara rutin, sehingga peralatan contohnya seperti kotak sampah
yang ada di setiap ruang kelas selalu dalam kondisi yang baik atau layak pakai.15
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 32
PP No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan yaitu sumber pembiayaan berasal dari
Pemerintah, Pemda dan masyarakat. Dana BOS yang didapatkan sekolah masuk kedalam kategori
sumber pembiayaan yang didapatkan dari pemerintah. Maka dari itu dalam perealisasiann dana
tersebut telah diatur oleh pemerintah sehingga sekolah tidak boleh melanggar melanggar aturan
yang telah ditentukan.
Penelitian Ebni (2015) mengenai implementasi kebijakan dana BOS di SD Kabupaten
Gunung Kidul, mengatakan penggunaan dana BOS yang pada kedua sekolah yaitu SDN RejoSari
dan SDIT Al-I‘Tisham masih kurang baik. Hal ini dikarenakan pihak sekolah melakukan
pemungutan uang kepada warga sekolah dikarenakan dana BOS yang didapatkan tidak mencukupi
untuk keperluan sekolah.
KESIMPULAN DAN SARAN
Sarana sumber air bersih secara keseluruhan sudah cukup baik, dengan dilihatnya pada SD
Negeri 234 Palembang telah memenuhi syarat berdasarkan Kepmenkes No. 1429 Tahun 2006,
sedangkan untuk SD Negeri 222 Palembang terdapat komponen yang belum memenuhi syarat
yaitu mengenai ketersdiaan dan kecukupan air bersih. Sarana jamban sudah cukup baik dengan
dilihatnya kedua sekolah telah memiliki jamban. Namun terdapat komponen penilaian yang belum
memenuhi syarat yaitu, jumlah jambannya masih belum memenuhi, untuk perlengkapan seperti
sabun yang tidak tersedia di setiap jamban, dan tidak tersedia gantungan pakaian pada jamban SD
Negeri 222 Palembang. Sarana SPAL pada SD Negeri 222 Palembang belum cukup baik, hal ini
diihat dari banyaknya sampah berserakan di pinggir SPAL dan terdapat juga sampah di dalam
SPAL tersebut. Sarana jamban pada SD Negeri 234 Palembang jauh lebih baik dibandingkan
dengan SD Negeri 222 Palembang. banyak komponen penilaian yang belum memenuhi syarat dari
hal kondisi fisik tempat pembuangan sampah dan cara pengolahan sampah tersebut. Perealisasian
sumber pembiayaan berupa dana BOS pada SD Negeri 234 Palembang jauh lebih baik
dibandngkan SD Negeri 222 Palembang, hal ini dapat dilihat dari jumlah petugas kebersihan hanya
satu orang dan fasilitas sarana sanitasi yang ada di sekolah masih banyak yang belum memenuhi
syarat.
DAFTAR PUSTAKA
1. Dickin S, Bisung E, Savadogo K. Sanitation and the commons: The role of collective action in
sanitation use. Geoforum. 2017;86:118-26.
2. Ngwenya BN, Thakadu OT, Phaladze NA, Bolaane B. Access to water and sanitation facilities
in primary schools: A neglected educational crisis in Ngamiland district in Botswana. Physics
and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C. 2018;105:231-8.
3. UNICEF. Sanitation: UNICEF; 2017 [cited 2017 September, 23].
4. Santi AUP, al Bahiij A. Kondisi Sanitasi Di Tiga Sekolah Dasar Negeri Di Daerah Tangerang
Selatan. Jurnal Holistika. 2018;2(1).
5. Widyatmoko S. Pengelolaan Dana BAntuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD N Kemasan I
Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta; 2017.
6. Ardillah Y, Sari IP, Windusari Y, editors. Association of Environmental Residential
Sanitation Factors to Communicable Disease Risk Among Musi Side-River Household in
Palembang, Indonesia: A Study of Slum Area. 2nd Sriwijaya International Conference of
Public Health (SICPH 2019); 2020: Atlantis Press.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 33
7. Thakadu OT, Ngwenya BN, Phaladze NA, Bolaane B. Sanitation and hygiene practices
among primary school learners in Ngamiland district, Botswana. Physics and Chemistry of the
Earth, Parts A/B/C. 2018;105:224-30.
8. Waluyo BH, Syarif A, Wahyunto AT, Sukiono, Dano A. Pedoman Pengembangan Sanitasi
Sekolah Dasar. In: Dasar DPS, editor. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
2018.
9. Shrestha A, Sharma S, Gerold J, Erismann S, Sagar S, Koju R, et al. Water Quality,
Sanitation, and Hygiene Conditions in Schools and Households in Dolakha and Ramechhap
Districts, Nepal: Results from A Cross-Sectional Survey. International journal of
environmental research and public health. 2017;14(1).
10. Karon AJ, Cronin AA, Cronk R, Hendrawan R. Improving water, sanitation, and hygiene in
schools in Indonesia: A cross-sectional assessment on sustaining infrastructural and
behavioral interventions. International Journal of Hygiene and Environmental Health.
2017;220(3):539-50.
11. Jewkes RK, O'Connor BH. Crisis in our schools: survey of sanitation facilities in schools in
Bloomsbury health district. BMJ : British Medical Journal. 1990;301(6760):1085.
12. Fanucchi MV. Drinking Water and Sanitation. In: Quah SR, editor. International
Encyclopedia of Public Health (Second Edition). Oxford: Academic Press; 2017. p. 350-60.
13. Caruso BA, Freeman MC, Garn JV, Dreibelbis R, Saboori S, Muga R, et al. Assessing the
impact of a school-based latrine cleaning and handwashing program on pupil absence in
Nyanza Province, Kenya: a cluster-randomized trial. Tropical medicine & international health
: TM & IH. 2014;19(10):1185-97.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 34
PENILAIAN RISIKO PAJANAN PESTISIDA DENGAN PENDEKATAN HIRA
(HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESMENT) PADA PETANI
PENGGUNA PESTISIDA
Rina Purwandari*, Sidiq Purwoko , Ina Kusrini
Balai Penelit ian dan Pengembangan Kesehatan Magelang, Badan Penelit ian dan
Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
Desa Kapling Jayan, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia
*Corresponding email: [email protected]
PESTICIDE EXPOSURE RISK ASSESSMENT USING HIRA (HAZARD
IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT) APPROACH TO FARMERS WHO USE
PESTICIDES
ABSTRACT
Environmental quality can be degraded by pesticides that used excessively. Pesticides are used by farmers to
control pests, weeds and diseases. The uncontrolled use of pesticides results in an imbalance of the
ecosystem due to the broad spectrum of killing power. On the other hand, pesticides have potential risks that
can reduce the health quality of farmers, consumers of farm products and the surrounding environment.
Management and risk control are needed so that the benefits of using pesticides can be obtained while the
risks that are harmful can be recognized. The research method was observation and interviews with a cross-
sectional research design. Data collection was carried out by observation and interviews with 109 farmers.
The risk assessment will be calculated by combining the level of opportunity and severity of the process
stages carried out using the HIRA (Hazard Identification And Risk Assessment) method. Based on the results
of this metod, there are two combinations of risks, low risk and medium risk. Moderate risk is acquired from
potential hazards of pesticide spray / fog and potential hazards of downwind spraying. Meanwhile, this is
low risk. All stages of the pesticide use process carried out a risk assessment where there is no potential risk
which has a high risk category (RT), medium risk (RS) is obtained in almost all potential hazards that exist in
the spraying process, and low risk (RS) is in the potential danger of the process of storing pesticides and
washing of pesticide spraying equipment.
Keywords: Environmental health, exposure, pesticides, risk assessment
ABSTRAK
Kualitas lingkungan dapat menurun dengan penggunaan pestisda yang berlebihan. Pestisida digunakan petani
untuk mengendalikan hama, gulma, dan peyakit. Penggunaan pestisida yang tidak terkendali mengakibatkan
ketidakseimbangan ekosistem karena daya bunuh (spketrum) yang luas. Pada sisi lain, pestisida memiliki
potensi risiko yang dapat menurunkan kualitas kesehatan petani, konsumen hasil tanaman dan lingkungan di
sekitarnya. Pengelolaan dan pengendalian risiko dibutuhkan agar nilai manfaat dari penggunaan pestisida
dapat tetap diperoleh sedangkan risiko yang merugikan dapat dikenali. Metode penelitian adalah observasi
dan wawancara dengan desain penelitian cross sectional. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan
wawancara pada 109 petani. Penilaian risiko akan dihitung dengan mengombinasikan tingkat peluang dan
tingkat keparahan dari tahapan proses yang dilakukan menggunakan metode HIRA (Hazard Identification
And Risk Assesment). Berdasarkan hasil penilaian risiko pajanan pestisida dengan pendektan metode HIRA
didapat dua kombinasi risiko yaitu risiko rendah dan risiko sedang. Risiko Sedang didapat pada potensi
bahaya buih/kabut semprotan pestisida dan potensi bahaya penyemprotan berlawanan arah angin. Sedangkan
selebihnya adalah risiko rendah. Semua tahapan proses penggunaan pestisida yang dilakukan penilaian risiko
tidak terdapat potensi risiko yang memiliki kategori risiko tinggi (RT), risiko sedang (RS) didapat pada
hampir seluruh potensi bahaya yang ada pada proses penyemprotan, dan risiko rendah (RS) terdapat pada
potensi bahaya dari proses penyimpanan pestisida dan pencucian peralatan penyemprotan pestisida.
Kata Kunci : Kesehatan Lingkungan, pajanan , pestisida , penilaian risiko
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 35
PENDAHULUAN
Terdapat ribuan pekerja dalam bidang pertanian yang terpapar bahan aktif pestisida setiap
tahun. World Health Organization (WHO) menyatakan dalam rilisnya sekitar 1 –- 5 juta kasus
keracunan pestisida pada pekerja di bidang pertanian dengan tingkat korban jiwa mencapai 220
ribu dan sekitar 80 persen keracunan tersebut terdapat di negara-negara berkembang setiap
tahunnya. Pada beberapa kasus, keracunan tersebut banyak ditemui pada tahapan mencampur dan
menyemprotkan pestisida oleh pekerja sektor pertanian. Industri pertanian tercatat sebagai
konsumen pestisida terbesar, sekitar 66 persen penggunaan pestisida di dunia antara tahun 2008-
2012 didominasi oleh pertanian.1.
Pestisida didefinisikan secara umum sebagai bahan kimia beracun yang dimanfaatkan untuk
mengendalikan hama dan jasad pengganggu yang merugikan manusia. Di Indonesia pestisida telah
cukup lama digunakan di bidang kesehatan lingkungan (bidang pemukiman dan rumah tangga) dan
utamanya adalah bidang pertanian.2 Teknologi tepat guna dalam program intensifikasi pertanian
diterapkan untuk meningkatkan produksi dalam. Pemanfaatan agrokimia, integrasi sektor pertanian
dengan berbagai bahan kimia dalam hal pengendalian hama maupun pemupukan tanaman
diperkenalkan secara masif menggantikan teknologi sebelumnya. Untuk meningkatkan hasil
produksi, petani dapat menggunakan 6-7 jenis pestisida insektisida dan fungisida sistemik dalam
satu kali masa tanam. Padahal, bahan pangan yang masih mengandung insektisida ini akan
termakan oleh manusia dan tentunya dapat menimbulkan efek dan berbahaya terhadap kesehatan
manusia3. Penggunaan pestisida yang di luar kontrol dan tidak terkendali dapat berakibat buruk
pada kesehatan petani itu sendiri dan lingkungan pada umumnya karena penggunaannya yang
begitu masif. Berbagai penelitian terkait dampak pestisida banyak sekali dilakukan, berbagai hasil
penelitian menunjukkan prevelensi keracunan tingkat sedang hingga berat disebabkan pekerjaan
pada sektor pertanian yakni antara 8,5 persen hingga persen.4
Beberapa kasus keracunan pestisida di sektor pertanian yang pernah dipublikasikan
diantaranya terjadi di Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang. Pada penelitian tersebut,
diketahui bahwa 14,3 persen petani sayuran yang diambil darahnya memiliki kadar kolinesterase
yang tidak normal 5. Penurunan kadar kholineterase dalam darah dapat menjadi indikasi adanya
residu pestisida dalam tubuh. Penelitian yang dilakukan oleh Purwandari menemukan indikasi
keracunan pada 7,3 persen petani sayuran di Kabupaten Karanganyar 6. Hasil analisis dari
penelitian lain yang dilakukan di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung
menunjukkan terdapat residu pestisida yang melampaui batas dari kadar yang diizinkan pada empat
sampel tanaman brokoli 7. Di Jawa Timur terdapat peningkatan angka keracunan pestisida sebesar
21 persen pada tahun 2009 setelah sebelum di tahun 2007 sekitar 12 persen 8.
Kementerian Pertanian merilis laporan peningkatan kebutuhan penggunaaan pestisida di
sektor pertanian dengan jumlah paling banyak adalah pestisida jenis insektisida 2. Laporan tersebut
menunjukkan ketergantungan petani di Indonesia terhadap penggunaan pestisida masih tinggi.
Penggunaan pestisida dapat membantu produktivitas komoditi pertanian, namun di sisi lain
penggunaan yang berlebihan dan tidak tepat justru dapat membahayakan kesehatan pekerja sektor
pertanian dan konsumen serta dapat berdampak pada pencemaran lingkungan 9. Bahan aktif
pestisida dapat digolongkan sebagai potensi bahan kimia apabila dilihat potensi dampak dan risiko
yang di timbulkannya, yang dalam ilmu kesehatan lingkungan masuk ke dalam katagori bahaya
lingkungan. Interaksi antara agen-agen lingkungan dengan manusia yang memiliki potensi
merugikan manusia disebut sebagai potensi bahaya lingkungan. Agen-agen tersebut dapat
diklasifikasikan sebagai bahaya fisik (radiasi energi, gelombang elektromagnetik, pencemaran
udara), bahaya biologi (organisme patogen, virus, bakteri) dan bahaya kimia (zat-zat toksik atau
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 36
beracun), perilaku hidup tidak sehat, dan faktor non fisik lingkungan 10
. Hasil penelitian Runia di
Ngablak, Magelang menunjukkan sebanyak 96,15 persen petani di sana mengalami keracunan
akibat penggunaan pestisida11
, sedangkan pada penelitian Gusti diketahui bahwa gejala neurotoksik
yang ditemukan pada responden dengan alat pelindung diri tidak lengkap lebih besar daripada
gejala neurotoksik (gangguan fungsi saraf) yang muncul pada responden dengan alat pelindung diri
lengkap12
.
Pestisida merupakan senyawa toksik yang dapat memicu efek karsinogenik maupun
nonkarsinogenik, tergantung jenis dan bahan pestisida13
. Potensi kerugian dari penggunaan
pestisida memunculkan pertanyaan seberapa besar risiko yang ditimbulkan oleh pestisida terhadap
kesehatan dan lingkungan, serta bagaimana risiko tersebut dapat dikelola dan dapat dikendalikan.
Pengelolaan dan pengendalian risiko dibutuhkan agar nilai manfaat dari penggunaan pestisida dapat
tetap diperoleh sedangkan risiko yang merugikan dapat dikenali. Tindak lanjut dari hasil tersebut
adalah meminimalkan risiko untuk kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya. Pengenalan
bahaya penggunaan pestisida yang berlebihan, diidentifikasi secara runtut dengan metode tertentu
agar tujuan pengenalan risiko tercapai. Tahapan selanjutnya adalah membuat mekanisme
pencegahan dan pengelolaan atas potensi bahaya yang teridentifikasi agar risiko yang berpotensi
muncul dapat diminimalkan atau bahkan dicegah kemunculannya.
Hazard Identification and Risk Assesment atau biasa disingkat sebagai HIRA adalah sebuah
metode identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko yang dipakai untuk melihat tingkat risiko
dari sebuah kegiatan 14
. HIRA digunakan dengan cara mengkuantifikasi potensi bahaya dengan
tingkat keparahan dari risiko yang berpotensi muncul dengan Peluang munculnya bahaya dalam
setiap tahapan dalam sebuah proses. Proses identifikasi yang dilakukan adalah mengenali seluruh
situasi atau kejadian yang di pandang berpotensi menimbulkan risiko. HIRA bertujuan memetakan
tingkat risiko yang berpotensi muncul dan menyajikannya dalam peringkat risiko. Peringkat risiko
yang tersaji dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan atau tindakan dalam upaya
mengendalikan risiko dan mencegah kerugian yang dapat muncul bila sewaktu-waktu risiko
tersebut muncul. HIRA akan menghasilkan peringkat risiko dari seluruh tahapan yang di nilai
dalam tiga tingkatan yaitu risiko tinggi, risiko sedang dan risiko rendah.
Metode HIRA digunakan dalam studi kasus yang dilakukan oleh Kurniawati, yang berhasil
mengelompokkan enam sumber bahaya dari 34 jenis temuan bahaya dalam produksi springbed.
Hasil penilaian risiko menunjukkan terdapat empat persen bahaya dalam katagori ekstrim, 81
persen bahaya dalam katagori risiko tinggi, dan 15 persen bahaya dalam katagori risiko sedang15
.
Identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko keselamatan dan kesehatan kerja di bagian
produksi hasil penelitian Puspitasari menunjukkan sumber bahaya kerja berasal dari faktor
pekerjaan pada manusia, peralatan atau mesin, dan lingkungan. Penurunan atau penghilangan risiko
di tempat kerja dapat menekan risiko kecelakaan dan penyakit seminimal mungkin16
. Identifikasi
bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko keselamatan dan kesehatan kerja dapat dilakukan di
setiap aktivitas lingkungan kerja yang memiliki potensi bahaya17
. Salah satu bagian penting dalam
penilaian risiko adalah penilaian pajanan. Pemajanan yaitu proses yang menyebabkan organisme
melakukan kontak dengan bahaya lingkungan dalam bentuk risk agent, sebagai jembatan
penghubung ―bahaya‖ dan ―risiko‖. Penggunaan pestisida sebagai bahan kimia diharapkan dapat
dikenali dan dikendalikan bahaya dan risikonya18
.
Mayoritas penduduk Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar bekerja di sektor
pertanian. Data dari kelurahan menunjukkan bahwa sebanyak 79,77 persen penduduknya memiliki
mata pencaharian sebagai petani maupun buruh tani (BPS Kab Karanganyar, 2013). Informasi lain
yang diperoleh adalah 80 persen petani di Kabupaten Karanganyar merupakan pengguna pestisida
dengan metode penyemprotan (spraying) 19. Penggunaan pestisida dengan metode penyemprotan
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 37
adalah metode yang rentan terhadap risiko terpajan bahan aktif pestisida melalui aliran intake
inhalasi atau masuknya bahan pajanan ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan, sehingga teknik
aplikasi yang benar dapat mencegah timbulnya risiko kesehatan pada penyemprot 20
. Apabila
mengingat penggunaan pestisida di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar yang masif
dalam beberapa tahun kebelakang, maka penting sekali untuk dapat melakukan penilaian risiko
aktivitas penyemprotan pestisida pada petani yang terpapar pestisida. Tujuan umum dari penilaian
risiko aktivitas penyemprotan adalah untuk mengetahui tahapan paling berisiko dalam proses
aktivitas tersebut.
Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkatan risiko yaitu risiko
tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah pada aktivitas penggunaan pestisida dalam setiap tahapan
proses pertanian di Kecamatan Ngargoyo Kabupaten Karanganyar. Manfaat dari penelitian ini
adalah diketahui tingkat risiko dari aktivitas penyemprotan pestisida baik itu tingkatan risiko
tinggi, risiko sedang dan risiko rendah di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. Setelah
tingkatan risiko diketahui, upaya pencegahan dan minimalisir risiko yang berpotensi merugikan
kesehatan dan lingkungan dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan terstruktur.
METODE
Metode penelitian ini diawali dengan melakukan observasi lapangan yaitu dengan
melakukan pengamatan aktivitas penyemprotan pestisida oleh petani. Pengamatan dilakukan pada
pencampuran pestisida, proses memasukkan ke tangki, penyemprotan, pencucian tangki dan
perlakuan kemasan bekas pestisida. Selain pengamatan, dilakukan juga proses wawancara dengan
petani penyemprot yang melakukan tahapan kerja tersebut. Wawancara dilakukan untuk menggali
lebih jauh potensi bahaya dalam pelaksanaan proses tersebut. Desain penelitian ini adalah
observasional secara potong lintang (cross sectional) yaitu observasi yang dilakukan secara
serentak pada individu-individu dari populasi tunggal pada satu saat atau periode. Jenis penelitian
adalah penelitian semi kuantitatif yaitu hasil pengamatan dilakukan diolah dengan
memperhitungkan tingkat keparahan dan tingkat frekuensi pajanan pestisida dengan menggunakan
metode HIRA (Hazard Identification And Risk Assesment). Penelitian dilakukan di Kecamatan
Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah pada periode Maret 2016 sampai
dengan Agustus 2016.
Populasi adalah semua petani di wilayah Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan sensus
pertanian tahun 2013 diketahui jumlah petani di kabupaten Karanganyar sebanyak 104.847 petani,
sedangkan untuk wilayah kecamatan Ngargoyoso sebanyak 6.301 orang 21
. Sampel dalam
penelitian ini adalah kelompok petani berjenis kelamin laki-laki dalam rentang umur 20-70 tahun di
Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. Pengambilan sampel dilakuan dengan rumus
penentuan jumlah sampel dari Taro Yamame dan Slovin dalam Ridwan dan Akdon yaitu apabila
populasi sudah diketahui 22
. Sampel yang ditentukan dari perhitungan berjumlah 98 petani, dengan
asumsi batas kesalahan yang diterima adalah 10% maka jumlah sampel yang diambil adalah 110.
Namun satu responden dinyatakan gagal sehingga jumlah sampel menjadi 109 sampel.
Kriteria inklusi yang ditetapkan untuk sampel adalah dapat berkomunikasi dengan baik,
pekerja atau buruh tani lebih dari satu tahun terakhir, menggunakan pestisida paling lama dua
minggu sebelum penelitian, dan bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar lebih dari lima tahun.
Kriteria eksklusi sampel adalah menderita sakit kronis, sedang menjalani pengobatan, dan
berencana pindah selama rentang waktu penelitian. Data umur, status gizi, tingkat pendidikan,
gambaran penggunaan pestisida petani serta tingkat pengetahuan mengenai alat pelindung diri
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 38
didapat dari kuisioner. Status gizi di peroleh pengukuran data antropometri meliputi berat badan
dan tinggi badan 23
.
Penilaian risiko akan dihitung dengan mengombinasikan tingkat peluang dan tingkat
keparahan dari tahapan proses yang dilakukan. Pengertian dari tingkat peluang dijelaskan dalam
tabel 1 di bawah ini:
Tabel 1. Tingkat Peluang
Tingkatan Kriteria Penjelasan
5 Most Likely (sering) Terjadi hampir pada semua keadaan
4 Likely (sering) sangat mungkin terjadi pada semua keadaan
3 Conseivable (cukup sering) Dapat terjadi sewaktu-waktu
2 Remote (agak sering) Mungkin terjadi sewaktu-waktu 1 Inconseivable (Jarang sekali) Hanya dapat terjadi pada keadaan tertentu
Sumber : Standard AS/NZS 4360
Tingkat peluang didefinisikan oleh Standard AS/NZS 4360 sebagai kemungkinan atau
likelihood yang diberi rentang dari suatu risiko yang jarang terjadi sampai risiko yang sering terjadi
setiap saat. Frekuensinya dapat diambil secara kualitatif melalui wawancara dengan petani
pengguna pestisida terkait 24
.
Tingkat keparahan dikategorikan antara kejadian yang tidak menimbulkan keracunan atau
cidera sampai pada tingkatan kejadian yang dapat berdampak pada kematian atau kerugian yang
sangat besar atau memiliki dampak yang panjang sampai terhentinya kegiatan pokok, dapat juga di
definisikan dengan kejadian yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial kecil hingga kerugian
yang besar. Penentuan tingkatan keparahan tersebut di dapat dengan pendekatan kualitatif melalui
wawancara dengan petani pengguna. Secara lebih terperinci, penjelasan tingkat keparahan ditulis
dalam tabel 2 berikut:
Tabel 2. Tingkat Keparahan
Level Kriteria Penjelasan
5 Catastrophic Berdampak pada kematian, kerugian sangat besar dan berdampak panjang sampai terhentinya kegiatan pokok
4 Major Keracunan Berat,kerugian besar, berpotensi menjadi penyakit serius
3 Moderate Keracunan sedang, perlu penanganan medis, kerugian finansial besar
2 Minor Keracunan ringan, kerugian finansial kecil 1 Insignificant Tidak terjadi keracunan, kerugian finansial kecil
Sumber : Standard AS/NZS 4360 dan Material Safety Data Sheet
Tahapan analisis diawali dengan identifikasi terhadap potensi bahaya terkait penggunaan
pestisida berdasarkan pengamatan di lapangan, alur proses penggunaan pestisida, aktivitas yang
dilakukan terkait penggunaan pestisida, dan kegiatan lain di area pertanian yang didapat dari petani
penggarap dan pemilik sawah. Data yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk menentukan
tingkat keparahan dan peluang kejadian, kedua data tersebut dikombinasikan dalam matriks risiko
untuk mengetahui tingkat risiko dari setiap tahapan. Hasil dari kombinasi tersebut akan
menunjukkan tingkat risiko dengan kategori risiko rendah, risiko menengah dan risiko tinggi
seperti yang dapat dijelaskan dalam tabel 3.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 39
Tabel 3. Matriks Risiko
Peluang Keparahan
1 2 3 4 5
5 5 10 15 20 25
4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5
Sumber : Standard AS/NZS 4360
Dengan kategori risiko sebagai berikut :
1. Risiko Rendah (RR); Warna hijau; Skor 1-5
2. Risiko Sedang (RS); Warna kuning; Skor 6-14
3. Risiko Tinggi (RT); Warna merah; skor 15-25
Skor yang didapat adalah perkalian atau kombinasi antara tingkat peluang dengan tingkat
keparahan dari setiap potensi bahaya yang diidentifikasi.
HASIL PENELITIAN
Dalam penelitian ini, gambaran umum kondisi responden di Kecamatan Ngargoyoso
Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa petani di Ngargoyoso masih berada pada usia
produktif.
Tabel 4. Gambaran Umum kondisi Responden
Variabel n % Rerata
Usia Kelompok usia 20-30 tahun 5 4.59
45,2 tahun
Rentang usia 31-40 tahun 30 27.52
Rentang usia 41-50 tahun 44 40.37
Rentang usia 51-60 tahun 24 22.02
Rentang usia 61-70 tahun 6 5.5
Tingkat Penidikan Petani
Tidak Sekolah 6 5.5
Tamat SD 51 46.8
Tamat SMP 30 27.5
Tamat SMA 19 17.4
Tamat D3 2 1.8
Tamat S1 1 0.9
Status Gizi
Kurus : 17.0 - 18.4 5 4.59
Normal : 18.5 - 25.0 87 79.82
Gemuk : 25.1 - 27.0 17 15.59
Dari 109 petani yang diwawancarai, 93 persen responden menjawab telah bekerja sebagai
petani selama lebih dari lima tahun. Petani yang bekerja paling lama waktunya adalah 40 tahun,
dengan rata-rata masa kerja petani adalah 17 tahun. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mereka
sudah menjalankan profesi sebagai petani sejak usia sekolah. Hal itu didukung dengan pendidikan
para petani yang sebagian besar tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dari
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 40
SMA. Pada Tabel. 4 diketahui bahwa sebagian besar petani hanya bersekolah sampai pendidikan
dasar, yaitu sebanyak 46,8 persen. Petani yang melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi
hanya sebesar 0,9 persen 25
.
Riwayat dan karakteristik petani dalam hal penggunaan pestisida pada saat melakukan
kegiatan pertanian ditunjukkan pada Tabel. 5. Dari data yang ditunjukkan dalam Tabel 5 diketahui
sebanyak 92,6 persen petani melakukan penyemprotan 1-5 kali seminggu. Kegiatan penyemprotan
dengan pestisida dilakukan pada pagi hari. Selama menyemprot, kebanyakan petani mengenakan
alat pelindung diri (APD) berupa jaket, topi, sepatu, dan masker. Arah penyemprotan sesuai dengan
arah angin. Pakaian yang dipakai ketika menyemprot merupakan baju khusus yang langsung
diganti setelah kegiatan pertanian selesai.
Tabel 5. Karakteristik Petani Berdasarkan Penggunaan Pestisida
Variabel n % Rerata
Lama menggunakan pestisida < 10 tahun 31 28.44
17.91 11-20 tahun 51 46.79
21-30 tahun 14 12.84
31-40 tahun 13 11.93
Waktu penyemprotan
Pagi Hari 109 100
Siang Hari 0 0
Sore Hari 0 0
Arah Penyemprotan
Sesuai arah angin 94 86.24
Berlawanan dengan arah angin 1 0.92
Tidak tentu 1 12.84
Penilaian risiko dengan pendekatan HIRA (Hazard Identification And Risk Assesment)
ditunjukkan dalam Tabel 6. Proses penilaian risiko diawali oleh proses identifikasi bahaya atau
hazard yang ada di sekitar petani pengguna pestisida. Proses identifikasi didasarkan atas proses
atau alur kegiatan yang dilakukan petani dalam berinteraksi dengan pestisida, alur tersebut terbagi
menjadi 6 proses yaitu penakaran pestisida, pencampuran pestisida, penyemprotan pestisida,
penyimpanan pestisida, pencucian peralatan penyemprotan, dan pembuangan kemasan pestisida.
Selanjutnya proses identifikasi dilakukan dengan menginventarisasi potensi bahaya yang mungkin
muncul. Bahaya tersebut dikatagorikan sebagai bahaya lingkungan. Interaksi antara agen-agen
lingkungan dengan manusia yang memiliki potensi merugikan manusia di sebut potensi bahaya
lingkungan, agen-agen tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bahaya fisik (radiasi energi,
gelombang elektromagnetik, pencemaran udara), bahaya biologi (organisme patogen, virus,
bakteri) dan bahaya kimia (zat-zat toksik atau beracun), perilaku hidup tidak sehat dan faktor non
fisik lingkungan 10
.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 41
Tabel 6. Hasil Penilaian Risiko
Proses Potensi
bahaya/Hazard Potensi Risiko/penyakit Peluang keparahan Grade Hasil
Penakaran Pestisida Bahan aktif pestisida Terhirup 2 2 4 Risiko Rendah
Tangan Kontak
dengan Bahan aktif
pestisida
Absorbsi bahan kimia
melalui kulit 2 2 4 Risiko Rendah
Pencampuran
Pestisida Bahan aktif pestisida
Iritasi pada kulit karena
kontak langsung 2 2 4 Risiko Rendah
Absorbsi bahan kimia
melalui kulit 2 2 4 Risiko Rendah
Terhirup 2 2 4 Risiko Rendah
Konsentrasi pestisida
melebihi dosis yang dianjurkan
Risiko keracunan 2 2 4 Risiko Rendah
Penyemprotan Kabut/buih
semprotan Pestisida Terhirup 3 3 9 Risiko Sedang
Iritasi pada mata 3 3 9 Risiko Sedang
Keracunan Pestisida 3 3 9 Risiko Sedang
Penyemprotan
berlawanan arah
angin
Terhirup 2 4 8 Risiko Sedang
Iritasi pada mata 2 4 8 Risiko Sedang
Iritasi pada kulit 2 4 8 Risiko Sedang
Absorbsi bahan kimia
melalui kulit 2 4 8 Risiko Sedang
Penyimpanan Pestisida
Penutup tidak rapat mudah tumpah
Terhirup 1 2 2 Risiko Rendah
Iritasi pada kulit 1 2 2 Risiko Rendah
Absorbsi bahan kimia melalui kulit
1 2 2 Risiko Rendah
Pencucian peralatan semprot
Sisa pestisida Terhirup 1 2 2 Risiko Rendah
Iritasi pada kulit 1 2 2 Risiko Rendah
Absorbsi bahan kimia melalui kulit
1 2 2 Risiko Rendah
Pembuangan
kemasan pestisida
Mencemari
lingkungan masuk kedalam tubuh 3 3 9 Risiko Sedang
Dari tabel 6 diketahui hasil bahaya yang telah teridentifikasi yang akan ditelusur potensi
risiko yang mungkin muncul dan berpotensi merugikan kesehatan petani dan lingkungan. Potensi
risiko diperoleh dari studi literatur seperti buku, lembar data keselamatan bahan kimia, wawancara
dengan petani dan informasi lainnya yang dapat dijadikan dasar penentuan risiko tersebut. Dari
proses identifikasi bahaya tersebut didapat 10 potensi bahaya. Dari 10 potensi bahaya ditemukan 20
potensi risiko yang dapat membahayakan kesehatan petani dan lingkungan.
Selanjutnya 20 potensi risiko tersebut akan uraikan tingkatannya kedalam level tingkat
bahaya dan tingkat keparahan sesuai dengan tabel 1 tentang tingkat peluang dan tabel 2 tentang
tingkat keparahan. Data tingkat peluang dan tingkat keparahan tersebut akan diperingkatkan
berdasarkan panduan dari standard yang dipublikasikan oleh Australians New Zealand Standard
tentang pengelolaan risiko dalam berbagai kondisi. Data yang telah berperingkat tadi, selanjutnya
dikombinasi dengan menggunakan matriks risiko. Dari hasil kombinasi tersebut setiap potensi
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 42
risiko yang telah terukur akan di kelompokkan atau dimasukkan kedalam kategori risiko rendah,
risiko sedang dan risiko tinggi.
Skor yang didapat adalah perkalian atau kombinasi antara tingkat peluang dengan tingkat
keparahan dari setiap potensi bahaya yang diidentifikasi. Dari hasil identifikasi didapat bahwa
potensi bahaya penyemprotan berlawanan arah angin dengan potensi risiko buih pestisida terhirup,
iritasi pada kulit, iritasi pada mata dan absorbsinya bahan pestisida ke kulit memiliki risiko tinggi
karena memiliki skor 16, sedangkan potensi bahaya penutupan tutup kemasan pestisida yang tidak
rapat dan pencucian peralatan semprot memiliki risiko rendah dikarenakan skor yang didapat
adalah 2.
PEMBAHASAN
Penilaian risiko yang dilakukan pada 6 tahapan proses penggunaan pestisida oleh petani di
Kecamatan Ngargoyoso menghasilkan 20 potensi risiko yang bila tidak dikendalikan dengan baik
berpotensi mengganggu kesehatan petani tersebut , ke-6 proses tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut :
a) Proses Penakaran Pestisida
Penakaran adalah tahapan awal dalam proses penyemprotan pestisida, pestisida dalam
kemasan akan ditakar sesuai ketentuan takaran dalam kemasan untuk selanjutnya di campur
dengan pelarut air pada tahapan berikutnya. Pada proses ini dibutuhkan konsentrasi oleh petani
sebagai penakar, karena bahaya ceceran bahan aktif pestisida dapat saja mengenai kulit dan bau
pestisida tersebut terhirup oleh petani. Pada proses ini potensi bahaya yang teridentifikasi adalah
keluarnya bahan aktif pestisida dari kemasan sehingga memungkinkan bahan tersebut uapnya
terhirup oleh petani, selain itu tangan sebagai media penakar sangat berisiko untuk terpapar
bahan aktif tersebut. Dalam proses ini dari pengamatan dan wawancara dengan petani didapat
tingkat peluang adalah 2 karena kondisi tersebut dapat terjadi namun jarang terjadi sedangkan
tingkat keparahan ada pada tingkatan 2 mengingat volume yang memapar sangatlah sedikit.
Dalam perhitungan kombinasi untuk proses penakaran pestisida memiliki 2 potensi risiko yaitu
terhirup dan absorsi bahan kimia pada kulit dengan tingkat risiko yaitu risiko rendah (RR)
dengan skor 4.
b) Proses Pencampuran Pestisida
Pada proses pencampuran pestisida teridentifikasi 2 potensi bahaya yaitu bahan aktif
pestisida dan pencampuran bahan aktif yang melebihi dosis yang dianjurkan. Untuk potensi
bahaya bahan aktif pestisida didapat 3 potensi risiko yang dapat membahayakan kesehatan yaitu
kontak langsung kulit dengan bahan aktif pestisida yang dapat menimbulkan iritasi kulit dan
terabsorbsinya bahan aktif pestisida tersebut melalui kulit serta terhirupnya uap bahan aktif
tersebut. Pada potensi bahaya aktif pestisida tersebut ketiga potensi risiko tersebut memiliki
tingkat peluang 2 dan tingkat keparahan 2 sehingga bila dikombinasi dalam matriks risiko di
dapat skor 4 atau masuk kedalam kategori risiko rendah (RR). Sedangkan untuk potensi bahaya
konsentrasi pestisida melebihi dosis didapat potensi risiko keracunan pestisida, keracunan dapat
terjadi bila pada dosis yang diberikan melebihi aturan dalam kemasan. Potensi risiko keracunan
tersebut dinilai memiliki tingkat peluang 2 dan tingkat keparahan 2 sehingga bila di kombinasi
dalam matriks risiko didapat skor 4 atau masuk ke dalam kategori risiko rendah (RR).
c) Proses Penyemprotan
Proses penyemprotan adalah proses paling kritis dalam semua tahapan proses, karena dalam
proses ini didapat 3 potensi bahaya yaitu kabut/buit semprotan pestisida, dan potensi bahaya
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 43
penyemprotan yang berlawanan arah angin. Untuk potensi bahaya buih semprotan pestisida
potensi risiko yang terdata adalah risiko terhirupnya buih tersebut, iritasi mata karena terkontak
buih pestisida yang disemprot dan potensi risiko keracunan karena bahan aktif pestisida yang
disemprotkan sangat berpotensi terserap tubuh dalam volume yang cukup dan dalam waktu yang
singkat. Pada potensi bahaya buih semprotan terdapat 3 potensi risiko yang tercatat, potensi
risiko tersebut adalah terhirup, iritasi pada mata dan potensi risiko keracunan pestisida, pada
aktivitas penyemprotan ini didapatkan tingkat peluang adalah 3 dan tingkat keparahan 3
sehingga pada kombinasi matriks risiko didapat skor risiko 9 yang dapat diartikan masuk ke
kategori risiko sedang (RS). Tingkat peluang mendapat skor 3 mengingat waktu pemajanan
dalam aktivitas yang relatif lama dibanding proses-proses lainnya bergantung pada luas lahan
yang disemprotkan, sedangkan tingkat keparahan mendapat skor 3, lebih dikarenakan waktu
penyemprotan yang lama dapat berpotensi meningkatkan volume bahan aktif pestisida yang
terserap ke tubuh.
Potensi bahaya penyemprotan berlawanan arah angin terdapat 4 potensi risiko yaitu terhirup,
terabsorbsi ke kulit, iritasi kulit dan iritasi mata. Pada kondisi ini walau penyemprotan
berlawanan arah angin tidak sering terjadi tapi dapat terjadi sewaktu-waktu dengan alasan
kurang fokusnya petani, terlupa melihat arah angin dan keteledoran lainnya untuk itu kondisi
tersebut memiliki tingkat peluang 2, sedangkan bila terjadi kondisi ini dapat berakibat sangat
fatal, karena kesalahan tersebut dapat meningkatkan terserapnya zat racun pestisida ke dalam
tubuh sehingga skor yang didapat adalah 4. Bila dikombinasikan kedalam matriks risiko ketiga
potensi bahaya tersebut mendapat skor 8 atau masuk ke dalam kategori risiko sedang (RS).
d) Penyimpanan Pestisida
Penyimpanan pestisida adalah proses yang dilakukan setelah proses penyemprotan, pada
proses ini potensi bahayanya adalah kekurangrapatan menutup penutup pestisida sehingga
memunculkan potensi risiko terhirup, iritasi kulit dan terserapnya bahan aktif pestisida melalui
kulit. Dari hasil pengamatan dan wawancara kondisi tersebut sangat jarang terjadi walau dapat
terjadi sewaktu-waktu untuk itu tingkat peluang kondisi tersebut adalah 1, namun demikian
bilapun terjadi tingkat keparahan yang didapat tidak terlalu tingga dikarenakan waktu terpapar
yang tidak lama, oleh karena hal tersebut skor yang didapat untuk tingkat keparahan adalah 2.
Bila dikombinasikan kedalam matriks risiko skor didapat adalah 4 dan masuk ke kategori risiko
rendah (RR).
e) Pencucian perlatan semprot
Dari hasil wawancara proses pencucian peralatan semprot sangat jarang dilakukan, rata-rata
pencucian tidak mengenal periode, sekedar mengikuti kebutuhan pencucian saja, selain hal
tersebut, pencucian biasanya dilakukan pada aliran irigasi saat aliran tersebut deras. Kondisi
tersebut membuat penilaia tingkat peluang ada di skor 1 dan tingkat keparahannya adalah 2,
sehingga bila di kombinasikan dalam matriks risiko didapat skor 2 atau masuk di kategori risiko
rendah (RR).
f) Pembuangan Kemasan Pestisida
Proses pembuangan kemasan pestisia adalah proses akhir pada penggunaan pestisida, proses
ini bergantung pada banyak tidaknya penggunaan pestisida oleh petani. Pada proses ini belum
pahamnya petani akan berbedanya perlakuan pembuangan kemasan bekas pestisida dengan
kemasan produk lainnya membuat beberapa petani melakukan proses pembuangan kemasan di
samakan dengan pembuangan limbah rumah tangga lainnya, kondisi tersebut tentunya sangat
berisiko mencemari lingkungan di sekitar lokasi pembuangan. Pada proses ini mengingat cukup
seringnya pola pembuangan kemasan bekas pestisida ke lokasi pembuangan domestik untuk
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 44
tingkat peluang dinilai pada skor 3, sedangkan tingkat keparahannya juga di nilai 3 mengingat
bila kondisi tersebut masih sering terjadi akan semakin mencemari lingkungan di sekitarnya.
Kombinasi matrik risiko pada proses ini adalah 9 atau masuk ke kategori risiko sedang (RS).
KESIMPULAN DAN SARAN
Proses penilaian risiko pada petani penggunaan pestisida didapat beberapa kesimpulan
sebagai berikut :
1) Pada proses penggunaan pestisida di kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar ini,
semua tahapan proses yang dilakukan penilaian risiko tidak terdapat potensi risiko yang
memiliki kategori risiko tinggi (RT), walau demikian perlu di lakukan pengawasan rutin
kepada petani terkait penggunaan pestisida mengingat potensi bahaya yang ditimbulkannya.
2) Risiko sedang (RS) didapat pada hampir seluruh potensi bahaya yang ada pada proses
penyemprotan, skor yang di dapat antara 8 sampai dengan 9, kondisi tersebut tentunya
membutuhkan perhatian lebih untuk di komunikasikan kepada petani agar potensi risiko yang
dapat muncul seperti terhirupnya uap pestisida, iritasi kulit dan mata akibat terkontak langsung
dan masuknya bahan kimia berbahaya yang berasal dari pestisida dapat dikendalikan atau
bahkan dicegah kemungkinan munculnya.
3) Potensi risiko yang dinilai sebagai risiko rendah (RS) terdapat pada potensi bahaya pada proses
penyimpanan pestisida dan pencucian peralatan penyemprotan pestisida. Kondisi tersebut
didapat karena pada proses tersebut, tingkat peluangnya kecil mengingat kondisi tersebut
jarang terjadi, walau tingkat keparahan yang didapat adalah sedang.
DAFTAR PUSTAKA
1. EPA. Pesticides Industry Sales and Usage. United Statyes Environ Prot Agency.
2017;(November):24.
2. Direktorat Pupuk Dan Pestisida. Pestisida Pertanian dan Kehutanan 2016. Jakarta:
Kementan RI; 2016.
3. Hartini E. Kontaminasi residu pestisida dalam buah melon (studi kasus pada petani di
kecamatan Penawangan). J Kesehat Masy. 2014;10(1):96–102.
4. Achmadi UF. Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah. Kompas. 2005;12.
5. Samosir K, Setiani O. Hubungan Pajanan Pestisida dengan Gangguan Keseimbangan Tubuh
Petani Hortikultura di Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang. J Kesehat Lingkung
Indones. 2017;16(2):63–9.
6. Purwandari R, Musoddaq MA, Fuada N. Profil Petani Sayur di Kabupaten Karanganyar
Berdasarkan Kadar Kholinesterase dan Fungsi Tiroidnya. J Ekol Kesehat. 2017;237–46.
7. Amilia E, Joy B, Sunardi D. Residu Pestisida pada Tanaman Hortikultura (Studi Kasus di
Desa Cihanjuang Rahayu Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat). J Agrik.
2016;27(1):2329.
8. Pawitra A. Pemakaian Pestisida Kimia Terhadap Enzim Choliterase dan Residu Pestisida
Dalam Tanah. UNAIR; 2011.
9. Yuantari M. Analisis Risiko Pejanan Pestisida Terhadap Kesehatan Petani. J Kesehat Masy.
2015;10:239–45.
10. Rahman A. Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan. In 2007.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 45
11. Runia YA. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Keracunan Pestisida Organofosfat,
Karbamat dan Kejadian Anemia pada Petani Hortikultura di Desa Tejosari Kecamatan
Ngablak Kabupaten Magelang. Universitas Diponegoro; 2008.
12. Gusti A. Faktor Yang Berhubungan Dengan Gejala Neurotoksik Akibat Paparan Pestisida
Pada Petani Sayuran Di Kenagarian Alahan Panjang Kabupaten Solok. J Kesehat Lingkung
Indones. 2017;16(1):17.
13. Maksuk. Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan terhadap Paparan Pestisida di Kawasan
Pertanian. Pros Semin Nas Lahan Suboptimal 2014. 2014;(September):714–9.
14. Ramli S. Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk Management.
Jakarta Dian Rakyat. 2010;
15. Kurniawati E, Sugiono, Yuniarti R. Analisis Potensi Kecelakaan Kerja pada Departemen
Produksi Sprigbed dengan Metode Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA)
(Studi Kasus : PT. Malindo Intitama Raya, Malang, Jawa Timur). J Rekayasa dan Manaj
Sist Ind. 2014;2(1):11–23.
16. Puspitasari N. Hazard Identifikasi dan Risk Assesment dalam Upaya Mengurangi Tingkat
Risiko di Bagian Produksi PT. Bina Guna Kimia Ungaran Semarang. Surakarta; 2010.
17. Prasetyo EH, Suroto, Kurniawan B. Analisis HIRA (Hazard Identification and Risk
Assessment) pada Instansi X di Semarang. J Kesehat Masy. 2018;6(5):519–28.
18. Djafri D. Prinsip Dan Metode Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan. J Kesehat Masy
Andalas. 2014;8(2):100.
19. Muhlisin A, Mahasiswa SS, FIK UMS Jln Yani Tromol Post KA, Muhlisin Dosen Jurusan
Keperawatan FIK UMS Jln Ahmad Yani Tromol Pos Pabelan Kartasura AI. Tingkat
Pengetahuan Bahaya Pestisida Dan Kebiasaan Pemakaian Alat Pelindung Diri Dilihat Dari
Munculnya Tanda Gejala Keracunan Pada Kelompok Tani Di Karanganyar. Tingkat
Pengetah Bahaya Pestisida. :154–64.
20. Hortikultura PP dan P. Teknik Penyemprotan Pestisida. Bogor; 2014.
21. BPS Kab.Karanganyar. Hasil Sensus Pertanian 2013 Kabupaten karanganyar. Karanganyar;
2013.
22. Riduwan A. Rumus dan data dalam analisis statistik. 1st ed. Bandung: Alfabeta; 2013.
23. Harahap H, Widodo Y, Mulyati S. Determining cut-off points of body mass index for
obesity. Persagi. 2005;1–12.
24. Australian NZS. Risk Management Standards 4360. 4360 Australian; 2004.
25. Purwandari R, Musoddaq MA, Khimayah, Nur‘aini N. Hubungan Residu Pestisida terhadap
Fungsi Tiroid Petani di Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Magelang; 2016.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 46
PREDIKSI BERAT LAHIR RENDAH MELALUI TREN KONSENTRASI
NITROGEN DIOKSIDA DI UDARA AMBIEN KOTA PALEMBANG
Dwi Septiawati
1*, Imelda G. Purba
2, Ani Nidia Listianti
2
1,2Bagian Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya
3Alumni Bagian K3KL Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya
Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662, Indonesia *Corresponding Email: [email protected]
PREDICTION OF LOW BIRTH WEIGHT THROUGH TREND OF NITROGEN DIOXIDE
CONCENTRATION IN AMBIENT AIR OF PALEMBANG CITY
ABSTRACT
This study aims to predict the occurrence of LBW by analyzing the relationship of LBW incidence trends with
the trend of NO2 concentration in the ambient air. This is ecological study design at 7 sub districts which
have measurement point of air quality 2012 until 2015. Aggregate data will be analyzed spatially and
predicted 1 year later. Prevalence of LBW for 2012-2015 in sequence is 1.9% of 14842 live births, 2.1% of
14443, 1.3% of 14838, and 1.1% of 14746. The average concentration of NO2 in ambient air 2012-2015 is
170.13 μg/m3/hr, 195.37 μg/m
3/hr, 216.97 μg/m
3/hr, and 430.23 μg/m
3/hr. The prediction of the occurrence of
BBLR in 2016 by analyzing the relationship of NO2 concentration trend in ambient air with the trend of
BBLR occurrence of Palembang City cannot be done because there is no relationship between the two
variables.
Keywords: Air Quality, Ecological Studies, LBW Prevalence, NO2 Concentration
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan memprediksi kejadian BBLR dengan cara menganalisi hubungan trend kejadian
BBLR dengan trend konsentrasi NO2 di udara ambien Kota Palembang secara geographical information
system. Studi ekologi ini dilakukan di 7 kecamatan yang terdapat titik pengukuran kualitas udara tahun 2012
sampai 2015. Data agregat akan dianalisis secara spasial dan diprediksi 1 tahun selanjutnya. Studi ini
menunjukkan prevalensi BBLR Tahun 2012-2015 adalah 1.9% dari 14842 kelahiran hidup, 2.1% dari 14443,
1.3% dari 14838, dan 1.1% dari 14746. Rata-rata kadar konsentrasi NO2 di udara ambien Tahun 2012-2015
adalah 170.13 µg/m3/jam, 195.37 µg/m
3/jam, 216.97 µg/m
3/jam, dan 430.23 µg/m
3/jam. Prediksi kejadian
BBLR tahun 2016 dengan cara menganalisi hubungan trend konsentrasi NO2 di udara ambient dengan trend
kejadian BBLR Kota Palembang, tidak dapat dilakukan karena tidak adanya hubungan diantara kedua
variabel tersebut.
Kata Kunci : Konsentrasi NO2, Kualitas Udara, Prevalensi BBLR, Studi Ekologi.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 47
PENDAHULUAN
Peningkatan pencemaran udara sejalan dengan meningkatnya penyakit akut dan kronis.
Berdasarkan 10 penyebab kematian dunia pada tahun 2011, penyakit akibat paparan polusi udara
beberapa diantaranya, seperti Infeksi Saluran Pernafasan dibawah (3,2 juta kasus), PPOK / PPOK
(3 juta kasus), Trakea bronkus & kanker paru-paru (1,5 juta kasus), dan kelahiran prematur (1,2
juta kasus).1 Pada 2013, UNICEF melaporkan 2,9 juta bayi di seluruh dunia meninggal dalam bulan
pertama kehidupan. Salah satu penyebabnya adalah riwayat berat badan lahir rendah yang tidak
segera mendapat penanganan serius.2 Berat Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi yang lahir dengan
berat kurang dari 2500 gram tanpa memandang usia kehamilan.3
Prevalensi BBLR di dunia sekitar 20,6 juta (15,5%) pada tahun 2011 dan 15,2% pada tahun
2012. Dari total kasus BBLR, 95,6% kasus berada di negara berkembang.3 Di Indonesia, menurut
hasil Riskesdas, prevalensi bayi berat lahir rendah (BBLR) menurun dari 11,5% pada 2007 menjadi
11,1% pada 2010 dan menjadi 10,2% pada 2013.4,5
Prevalensi BBLR di Provinsi Sumatera Selatan
9,3%.5 Kota Palembang, berdasarkan laporan program anak, jumlah kematian bayi tahun 2012
sebanyak 97 kematian bayi dari 29.451 kelahiran hidup dengan penyebab kematian antara lain
asfiksia, BBLR, kelainan kongenital, pneumonia , dan penyebab lainnya.6 Dari 29.235 kelahiran
hidup, terdapat 319 (1,13%) kasus BBLR.7
Sejumlah penelitian telah menemukan bukti yang mendukung hipotesis bahwa polusi udara
dapat meningkatkan risiko gangguan pertumbuhan janin.8,9
NO2 menjadi salah satu variabel minat
dalam beberapa penelitian untuk melihat pengaruhnya terhadap hasil kelahiran.10,11,12,13,14,15
Penelitian ini merupakan penelitian sebagai bentuk perlindungan berdasarkan bukti akademis dari
suatu dampak pencemaran udara dan diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pihak
terkait untuk melakukan pengelolaan sanitasi lingkungan sebagai bentuk upaya preventif terhadap
kejadian atau kejadian terkait kesehatan lingkungan. gangguan.
METODE
Penelitian ini dilakukan untuk merepresentasikan kondisi lingkungan (konsentrasi NO2 di
udara ambien) dan dampaknya terhadap kesehatan (kasus BBLR) di Kota Palembang. Dalam studi
ini, studi ekologi digunakan untuk menganalisis dugaan korelasi antara variabel bebas (konsentrasi
NO2 di udara ambien) dengan variabel terikat (kasus BBLR) dengan menggunakan data agregat
berdasarkan batas wilayah geografis. Semua kelahiran hidup dengan berat badan lahir rendah (˂
2.500 gram) di setiap kecamatan per tahun menjadi unit yang akan diteliti. Data konsentrasi NO2 di
udara ambien merupakan data agregat per tahun, yang selanjutnya akan dianalisis secara statistik,
spasial, dan diproyeksikan atau diprediksi dalam 1 tahun ke depan. Perbandingan geografis
berdasarkan konsentrasi pajanan NO2 di udara ambien dan prevalensi kasus BBLR di Kota
Palembang dibuat berdasarkan wilayah geografis (kecamatan) yang menjadi titik tolak ukur
kualitas udara di Kota Palembang. Variasi prevalensi BBLR di setiap kecamatan akan
berkontribusi pada hipotesis penyebab yang mendasari dan menunjukkan kemungkinan korelasi
dampak pencemaran udara oleh NO2.
Populasi penelitian dalam penelitian ini adalah semua kelahiran hidup di Kota Palembang
Sumatera Selatan Tahun 2015. Sampel penelitian ini adalah data agregat tentang kualitas udara
khususnya konsentrasi NO2 tahun 2012 sampai 2015 di Kota Palembang yang akan diperoleh dari
pengukuran udara. Kualitas Kota Palembang menurut Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota
Palembang dan data kasus BBLR di Kota Palembang Tahun 2012-2015 diperoleh dari laporan
kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palembang. Kedua data tersebut akan divisualisasikan secara
geografis pada pemetaan dengan Sistem Informasi Geografis menggunakan shapefile Kota
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 48
Palembang berdasarkan wilayah kecamatan yang akan diperoleh dari Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palembang dengan juga menggabungkan koordinat lokasi
titik pengambilan sampel Pengukuran kualitas udara Kota Palembang menurut tahun pengukuran
menggunakan data primer hasil pengukuran GPS.
HASIL PENELITIAN
Jumlah kelahiran hidup di Kota Palembang dari tahun 2012 hingga 2015 sangat dinamis,
meningkat pada tahun 2013, menurun selama 2 tahun berikutnya (2014-2015) (Tabel 1). Kasus
BBLR di Kota Palembang, dari tahun 2012 meningkat pada tahun 2013, namun terus menurun
hingga tahun 2015 (Tabel 1). Grafik 1 menjelaskan bahwa Kecamatan Seberang Ulu 1 merupakan
kabupaten dengan jumlah rata-rata kasus BBLR tertinggi dibandingkan lokasi penelitian lain di
Kota Palembang selama tahun 2012-2015. Kecamatan Kertapati merupakan kabupaten dengan
jumlah rata-rata kasus BBLR terendah. Kecamatan Seberang Ulu 1, Ilir Timur 1, dan Kemuning
mengalami peningkatan rata-rata jumlah kasus BBLR pada Tahun 2015 dan Kabupaten Ilir Barat 1
mengalami peningkatan rata-rata jumlah kasus BBLR pada tahun 2015.
Tabel 1.Distribusi Frekuensi Kelahiran Hidup dan Kasus BBLR di Lokasi PenelitianKota
Palembang Tahun 2012-2015
Kecamatan Lahir Hidup BBLR
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
Σ % Σ % Σ % Σ %
Seberang Ulu I 3390 3339 3501 3429 53 1.56 96 2.88 49 1.40 43 1.25
Kertapati 1674 1506 1534 1589 27 1.61 27 1.79 7 0.46 4 0.25
Ilir Barat I 2473 2530 2518 2539 59 2.39 51 2.02 35 1.39 48 1.89
Ilir Timur I 958 988 983 974 18 1.88 40 4.05 27 2.75 17 1.75
Kemuning 1566 1537 1643 1586 21 1.34 24 1.56 21 1.28 14 0.88
Ilir Timur II 3001 2820 2798 2801 64 2.13 38 1.35 28 1.00 9 0.32
Kalidoni 1780 1723 1861 1828 46 2.58 39 2.26 27 1.45 26 1.42
TOTAL 14842 14443 14838 14746 288 1.9 315 2.1 194 1.3 161 1.1
Rata-rata konsentrasi NO2 di udara ambien Kota Palembang dari tahun 2012 hingga 2015
berkisar antara 71,55 μg /m3/jam hingga 656,7 μg /m
3/jam. Pada tahun 2015 terdapat empat
kecamatan dengan rata-rata konsentrasi NO2 di atas Baku Mutu Lingkungan pencemar NO2 di
udara ambien, yaitu Seberang Ulu 1, Kertapati, Ilir Barat 1, dan Ilir Timur 1 (Grafik 1). Apabila
penjumlahan setiap hasil pengukuran dalam periode pengukuran tahunan adalah maka konsentrasi
rata-rata NO2 sejak tahun 2012 terus mengalami peningkatan dari rata-rata konsentrasi tersebut
setiap tahunnya. Kecamatan yang mengalami penurunan konsentrasi rata-rata pada tahun 2014
dibandingkan tahun sebelumnya (2013) adalah Kecamatan Seberang Ulu 1 dan Kalidoni (Grafik 1).
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 49
Analisis spasial konsentrasi NO2 di udara ambien dan kejadian BBLR digunakan untuk
menyelidiki dan mengeksplorasi data dari perspektif spasial. Pola hubungan konsentrasi NO2 di
udara ambien dengan kejadian BBLR di Kota Palembang secara regional dapat dilihat melalui
analisis peta tematik hasil overlay konsentrasi NO2 di udara ambien dengan prevalensi kejadian
BBLR. Data konsentrasi NO2 di area pengukuran dan data kejadian BBLR yang terkumpul
dianalisis menggunakan GIS (Geographic Information System) menggunakan software Arcview.
Analisis spasial dalam penelitian ini menggunakan peta dasar Kota Palembang. Konsentrasi NO2
pada tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 di kecamatan lokasi penelitian divisualisasikan dengan
degradasi warna menggunakan rentang nilai konsentrasi NO2. Jumlah kelas dan rentang kategori
kelas yang diwakili oleh degradasi warna didasarkan pada Kep-107/KABAPEDAL/11/1997
tentang Pedoman Teknis Penghitungan dan Pelaporan serta Informasi Indeks Polusi Udara Standar.
Grafik 1
Tren Konsentrasi NO2 di Udara Ambien di Lokasi Penelitian
Kota Palembang Tahun 2012-2015
Visualisasi kejadian BBLR di Kota Palembang dari tahun 2012 hingga 2015 akan
ditampilkan pada Gambar 2. Kasus tersebar di peta tematik berdasarkan wilayah administratif yang
dapat menggambarkan sebaran kasus. Kasus diilustrasikan dengan simbol titik hitam (t) dan titik
putih (○) pada peta. Intinya tidak mewakili letak perkara di wilayah administrasi kecamatan tetapi
mewakili jumlah perkara di wilayah administrasi. Simbol titik hitam (●) mewakili jumlah kasus
BBLR sebanyak 5 kasus, sedangkan titik putih (○) mewakili 1 kasus BBLR.
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
2012 2013 2014 2015
Ko
nse
ntr
asi N
O2
(µg/
m3/j
am)
Tahun
Seberang Ulu I
Kertapati
Ilir Barat I
Ilir Timur I
Kemuning
Ilir Timur II
Kalidoni
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 50
Gambar 1
Prediksi Konsentrasi NO2 di Udara Ambien Kota Palembang Tahun 2016
Tahun 2012 Tahun 2013
Tahun 2015 Tahun 2014
Prediksi Tahun 2016
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 51
Gambar 2
Prediksi Kasus BBLR di Kota Palembang Tahun 2016
Tahun 2012 Tahun 2013
Tahun 2015 Tahun 2014
Prediksi Tahun 2016
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 52
Pada tahun 2012 kasus BBLR Palembang secara umum masih rendah yaitu 1,9% dari 14.442
kelahiran. Dari 7 kecamatan yang diamati, kasus BBLR terbanyak berada di Kecamatan Ilir Timur
II dengan 64 kasus dari 3001 kelahiran hidup, namun prevalensi tertinggi kasus BBLR berada di
Kecamatan Kalidoni sebesar 2,58% dari 1.780 kelahiran hidup. Pada tahun 2013 kasus BBLR
meningkat 27 kasus dan prevalensinya meningkat menjadi 2,1% dari 1.4443 kelahiran hidup pada
tahun 2013 di Kota Palembang. Pada tahun 2013 terdapat 4 kabupaten yang mengalami
peningkatan prevalensi kejadian BBLR (Seberang Ulu I, Kertapati, Ilir Timur I dan Kemuning)
dengan Kabupaten Ilir Timur I menjadi prevalensi tertinggi kasus BBLR. Pada tahun 2014 jumlah
kasus dan prevalensi kejadian BBLR menurun hampir 50%. Distrik Ilir Timur I tetap menjadi
kecamatan dengan prevalensi kasus BBLR tertinggi. Kecamatan Seberang Ulu I merupakan kasus
BBLR tertinggi pada tahun 2014. Setahun terakhir pengamatan (Tahun 2015), kasus BBLR juga
mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan. Namun demikian, Kabupaten Ilir Barat I
menjadi satu-satunya kecamatan yang mengalami jumlah kasus BBLR dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya. Prevalensi tertinggi kasus BBLR pada Tahun 2015 juga terjadi di Kabupaten Ilir Barat
I.
PEMBAHASAN
Pada tahun 2012, kualitas udara Kota Palembang secara umum dikategorikan tidak sehat
karena konsentrasi NO2 di udara ambien berkisar antara 100-199 μg/m3/jam dengan konsentrasi
maksimum 179,45 μg/m3/jam di Kecamatan Kertapati dan konsentrasi minimum. yaitu 153,75
μg/m3/jam di Kecamatan Ilir Timur II. Terdapat 2 kecamatan yang mengalami peningkatan status
kategori kualitas udara pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012. Kecamatan Ilir Barat I dan Ilir
Timur II yang mengalami peningkatan status kualitas udara menjadi sangat tidak sehat dengan nilai
konsentrasi NO2 di udara ambien adalah antara 200-299 μg/m3/jam. Kecamatan lainnya masih
berstatus kualitas udara tidak sehat dengan nilai konsentrasi NO2 di udara ambien berkisar antara
100-199 μg/m3/jam. Pada tahun 2014, 4 kecamatan mengalami peningkatan kualitas udara ambien.
Kecamatan Ilir Barat I menjadi kecamatan yang dalam 3 tahun terus mengalami status kualitas
udara ambien (penurunan kualitas udara) yang pada tahun 2013 berstatus sangat tidak sehat, pada
tahun 2014 statusnya menjadi berbahaya dimana nilai konsentrasi NO2 di udara ambien adalah ≥
300 μg/m3/jam. 3 Kecamatan lainnya (Kemuning, Ilir Timur 1 dan Kertapati) mengalami
peningkatan status dari tidak sehat menjadi sangat tidak sehat dengan kisaran nilai konsentrasi
antara 200-299 μg/m3/jam. Pada tahun pengamatan terakhir yaitu Tahun 2015, hampir semua
kabupaten yang diamati mengalami peningkatan kualitas udara menjadi berbahaya dengan nilai
konsentrasi NO2 di udara ambien ≥ 300 μg/m3/jam. Hanya 1 kecamatan (Kalidoni) dari 7
kecamatan yang diamati masih berstatus kualitas udara tidak sehat dengan nilai konsentrasi NO2 di
udara ambien berkisar antara 200-299 μg/m3/jam.
Berdasarkan hasil analisis spasial dapat disimpulkan bahwa konsentrasi NO2 di kota
Palembang secara umum dan di 7 kecamatan lokasi penelitian khususnya terus meningkat setiap
tahunnya (Gambar 1). Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan peningkatan aktivitas lalu lintas
dan aktivitas pembangunan fisik yang terjadi di Kota Palembang. Aktivitas lalu lintas, terutama
emisi kendaraan bermotor dan asap alat berat serta proses pembakaran yang tidak sempurna selama
konstruksi menjadi sumber emisi gas NO2 ke udara ambien. Peningkatan gas NO2 ini tentunya
berimplikasi pada efek kesehatan akibat paparan NO2. Salah satu dampak tersehat yang telah
diteliti secara ekstensif terkait dengan paparan NO2 di udara ambien pada ibu hamil selama
kehamilan adalah kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 53
Berdasarkan hasil analisis spasial dapat disimpulkan bahwa meskipun mengalami
peningkatan jumlah kasus dan prevalensi kejadian BBLR, namun secara umum terdapat
kecenderungan penurunan kasus dan prevalensi BBLR di Kota Palembang di umum dan di 7
kabupaten yang diamati secara khusus (Gambar 2). Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis
spasial kecenderungan konsentrasi NO2 di udara ambien terhadap kecenderungan kejadian BBLR
Kota Palembang dengan cara overlay peta konsentrasi NO2 ke peta kasus BBLR. Dari hasil analisis
spasial kecenderungan konsentrasi NO2 di udara ambien terhadap kecenderungan terjadinya BBLR
Kota Palembang. Konsentrasi NO2 di udara ambien kemudian dilapisi dengan penyebaran kasus
BBLR di Kota Palembang 2012. Tahun 2013 menunjukkan hubungan yang signifikan antara
konsentrasi NO2 di udara ambien dengan kejadian BBLR di Kota Palembang pada tahun 2013. Hal
ini terlihat dari arah hubungan paralel dimana konsentrasi NO2 pada tahun 2013 secara umum
meningkat dan diikuti dengan peningkatan kasus dan prevalensi kejadian BBLR. Hasil analisis
spasial tahun 2014 menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara konsentrasi
NO2 di udara ambien dengan kejadian BBLR. Hal ini terlihat dari gambaran konsentrasi NO2 yang
terus meningkat namun tidak terjadi pada kasus dan prevalensi BBLR. Pada tahun 2014 terjadi
penurunan kasus dan prevalensi kejadian BBLR di Kota Palembang. Hal yang sama juga terlihat
dari hasil analisis spasial tahun 2015. Berdasarkan hasil analisis spasial secara umum dapat
disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara konsentrasi NO2 di udara
ambien dengan kejadian BBLR di Kota Palembang. Hal ini dikarenakan konsentrasi NO2 yang
terus meningkat tidak diikuti dengan kasus BBLR. Kasus dan prevalensi BBLR di Kota Palembang
selama periode observasi cenderung menurun.
Prediksi kasus BBLR pada tahun 2016 dengan mengaitkannya dengan trend konsentrasi NO2
di udara ambien tidak dapat dilakukan karena tidak ada hubungan yang signifikan yang diperoleh
dari hasil analisis spasial. Prediksi tetap dilakukan namun terhadap masing-masing variabel yaitu
trend konsentrasi NO2 di udara ambien Kota Palembang dan trend kasus BBLR di Kota Palembang
tahun 2016. Prediksi dilakukan dengan asumsi keadaan minimal sama dengan 1 tahun sebelumnya
dan tanpa upaya perbaikan atau peningkatan kualitas. Jika dari tahun 2015 tidak dilakukan upaya
penyehatan lingkungan maka dapat diprediksi trend konsentrasi NO2 seperti pada Gambar 1.
Prediksi kasus BBLR di Kota Palembang tahun 2016 dilakukan dengan asumsi keadaan minimal
sama dengan 1 tahun sebelumnya dan tanpa adanya upaya perbaikan atau peningkatan kualitas.
secara signifikan (Gambar 2).
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis spasial atau pemetaan jumlah kejadian BBLR di Kota Palembang
dari tahun 2012-2015 dapat diketahui bahwa terdapat tren penurunan jumlah kasus dan prevalensi
kejadian BBLR. Konsentrasi NO2 di udara tahun 2012-2015 di Kota Palembang menunjukkan
adanya kecenderungan peningkatan konsentrasi NO2 di udara ambien. Tidak ada hubungan yang
signifikan antara kecenderungan konsentrasi NO2 di udara ambien dengan kecenderungan kejadian
BBLR Kota Palembang. Prediksi kejadian BBLR tahun 2016 tidak dapat dilakukan dengan
menganalisis hubungan trend konsentrasi NO2 di udara ambien dengan trend kejadian BBLR Kota
Palembang karena tidak ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Prediksi tetap dilakukan
tetapi untuk masing-masing variabel secara individual dengan mempelajari trend masing-masing
variabel.
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran yang
bertujuan untuk mengurangi konsentrasi NO2 di udara ambien maupun menurunkan risiko kejadian
BBLR seperti; Manajemen transportasi, Manajemen lingkungan, Merancang kegiatan peningkatan
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 54
kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pencemaran udara, Upaya penyehatan lingkungan,
khususnya penyehatan udara oleh sektor kesehatan (Dinas Kesehatan Kota Palembang, BTKL PPM
Palembang dan Puskesmas), dan Tindakan atau upaya perlindungan dari dampak polutan udara
ambien yang dapat dilakukan oleh ibu hamil di Kota Palembang.
DAFTAR PUSTAKA
1. WHO. (2013). The Top 10 Causes of Death: The 10 Leading Causes of Death in the World,
2000 and 2011
2. IGME, U. I.-A. G. o. C. M. E. U. (2014). Levels and Trends in Child Mortality; Report 2013
New York: UNICEF.
3. WHO. (2011). WHO Guidelines on Preventing Early Pregnancy and Poor Reproductive
Outcomes Among Adolescents in Developing Countries. Geneva, Switzerland: World Health
Organization.
4. Litbangkes. (2007). Riset Nasional Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007. Jakarta: Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia.
5. Litbangkes. (2013). Riset Nasional Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013. Jakarta: Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia.
6. Dinkes. (2014). Profil Kesehatan Kota Palembang 2014. Palembang: Dinas Kesehatan Kota
Palembang.
7. Dinkes. (2015). Profil Kesehatan Kota Palembang 2014. Palembang: Dinas Kesehatan Kota
Palembang.
8. Bell, e. a. (2007 ). Ambient Air Pollution and Low Birth Weight in Connecticut and
Massachuset. Environmental Health Perspectives, 115, 1118-1124.
9. Brauer, e. a. (2008). A Cohort Study of Traffic Related Air Pollution Impacts on Birth
Outcomes. Environmental Health Perspectives(116), 680-686.
10. Abusalah, A., Gavana, M., Haidich, A.-B., Smyrnakis, E., Papadakis, N., Papanikolaou, A., &
Benos, A. (2011). Low Birth Weight and Prenatal Exposure to Indoor Pollution from Tobacco
Smoke and Wood Fuel Smoke: A Matched Case–Control Study in Gaza Strip. Maternal
Children Health Journal, 16, 1718–1727. doi: DOI 10.1007/s10995-011-0851-4
11. Ballester F, E. M., Iniguez C, Llop S, Ramon R, Esplugues A (2010). Air Pollution Exposure
during Pregnancy and Reduced Birth Size: A Prospective Birth Cohort Study in Valencia,
Spain. Environmental Health Perspective, 9(6).
12. Fitria, L., Wulandari, R. A., Hermawati, E., & Susanna, D. (2008). Kualitas udara dalam ruang
perpustakaan universitas ‖x‖ ditinjau dari kualitas biologi, fisik, dan kimiawi. Makara,
kesehatan, 12( 2 ), 76-82.
13. Llop S, e. a. (2010). Preterm Birth and Exposure to Air Pollutants during Pregnancy. Environ
Res.
14. Salam MT, e. a. (2005). Birth Outcomes and Prenatal Exposure to Ozone, Carbon Monoxide,
and Particulate Matter: Results from the Children's Health Study. Environmental Health
Perspective(113), 1638–1644.
15. Siddiqui, A. R., Gold, E. B., Yang, X., Lee, K., Brown, K. H., & Bhutta, Z. A. (2008). Prenatal
Exposure to Wood Fuel Smoke and Low Birth Weight. Environmental Health Perspectives,
4(116).
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 55
GEJALA KLINIS PENYAKIT COVID-19 PADA BAYI DAN ANAK : STUDI
LITERATUR
Komalasari,
1* Ade Tyas Mayasari,
2 Elsa Fitri Ana
3
1,2,3Midwifery Department, Health Faculty, Universitas Aisyah Pringsewu, Lampung
Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, Lampung
*Corresponding email: [email protected]
ABSTRACT
World Health Organization (WHO) has declared the status of Covid-19 as a global pandemic on March 11,
2020 in Geneva, Switzerland. This epidemic affects all of age groups. However, many information on this age
group is not yet available. Therefore, we need to have informations about clear symptoms in the clinical
symptoms of infants and children Covid-19 virus infection. This study aims to discuss articles that have been
published regarding the clinical symptoms of Covid-19 virus infection in infants and children. There are 7
articles taken in this research. Articles taken from February to September 2020. The results of the 7 articles
will be analyzed and discussed regarding clinical symptoms in infants and children. A total of 2,205 babies
and children were sampled in this study. More than 90% of the clinical symptoms of Covid-19 infection in
infants and children are asymptomatic, mild, moderate to severe. The spread of Covid-19 occurs due to
direct contact with adults who are infected with Covid-19 and have a history of travel to epidemic areas.
Infants and children have milder clinical symptoms of Covid-19 infection than adults.
Keyword: Clinical characteristics, Covid-19, infant, Children
ABSTRAK
World Health Organization (WHO) telah menetapkan status Covid-19 sebagai pandemi global pada tanggal
11 Maret 2020 di Jenewa, Swiss. Wabah ini menyerang seluruh kelompok usia. Namun, informasi pada
kelompok usia anak masih sedikit. Oleh karena itu, perlu adanya informasi mengenai karakteristik yang jelas
tentang gejala klinis infeksi virus Covid-19 pada bayi dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas
artikel-artikel yang telah terbit mengenai gejala klinis infeksi virus Covid-19 pada bayi dan anak. Terdapat 7
artikel yang diambil dalam penelitian ini. Artikel diambil dari bulan Februari sampai September Tahun 2020.
Hasil penelitian dari 7 artikel tersebut akan dianalisis dan dibahas mengenai gejala klinis pada bayi dan anak.
Sebanyak 2.205 bayi dan anak menjadi sampel dalam penelitian ini. Lebih dari 90% gejala klinis infeksi
Covid-19 pada bayi dan anak bersifat asimtomatik, ringan, sedang sampai berat. Penyebaran penyakit Covid-
19 terjadi akibat kontak langsung dengan orang dewasa yang terinfeksi Covid-19 dan memiliki riwayat
perjalanan ke daerah epidemi. Bayi dan anak memiliki gejala klinis infeksi Covid-19 relatif ringan
dibandingkan dengan orang dewasa.
Kata kunci: Gejala klinis, infeksi virus, Covid-19, bayi, anak.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 56
PENDAHULUAN
Penyakit Covid-19 pertama kali muncul di China pada akhir Desember Tahun 2019. World
Health Organization (WHO) telah menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global darurat
kesehatan.1,2,3,4
Data bulan April Tahun 2020 menyebutkan 1,7 juta orang telah terinfeksi virus
Covid-19 dan setidaknya 18.433 orang telah meninggal karena virus ini.5
Penyakit Covid-19
disebabkan oleh Corona virus yang merupakan virus RNA dari family Coronaviridae dan subfamily
Coronavirinae. Virus ini menyebabkan sindrom pernapasan akut yang mirip dengan gejala
penyakit SARS-CoV sehingga dinamakan Coronavirus 2 (SARS-CoV-2).6,7
Penyakit Covid-19 menimbulkan gejala klinis ringan sampai berat. Gejalanya meliputi batuk
kering, demam tinggi, nyeri dada, lemah, lesu, nyeri otot dan diare. Semua kelompok usia telah
terinfeksi penyakit ini, termasuk bayi dan anak.8,9,10
Penyakit ini akan menimbulkan gejala yang
lebih ringan pada kelompok usia anak dibandingkan pada kelompok usia orang dewasa. Gejala
yang timbul tidak spesifik pada kelompok neonatus dan bayi. Presentasi Covid-19 pada kelompok
usia anak bersifat asimtomatik hingga gangguan pernapasan yang parah.11
Oleh karena itu, perlu
adanya karakteristik yang jelas mengenai gejala klinis Covid-19 pada bayi dan anak yang termasuk
dalam kelompok usia rentan.
METODE Desain Studi
Penelitian ini disusun berdasarkan sumber pustaka dengan cara mengumpulkan data dari
artikel jurnal, terkait tema dan masalah yang dianalisis.
Pencarian Artikel yang relevan
Pencarian dilakukan menggunakan kata kunci dalam bahasa inggris. Pencarian artikel
dilakukan pada bulan September Tahun 2020 dengan menggunakan kata kunci ―Clinical
characteristics, Covid-19, neonatal, infant, newborn, children, SARS-CoV-2‖.
Seleksi Kriteria Inklusi dan eksklusi
Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah artikel yang diterbitkan sebagai studi kasus,
laporan kasus dan studi observasi mulai 1 Februari 2020 sampai 30 September 2020, Sedangkan
kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah artikel yang berupa review jurnal. Terdapat 7 artikel
yang sesuai dengan tema dan diambil dalam penelitian ini.
HASIL PENELITIAN
Penelitian ini menganalisis tujuh artikel jurnal. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak
2.205 bayi dan anak dengan infeksi Covid-19 yang berusia 0 – 16 tahun. Sampel dalam penelitian
diambil dari tiga Negara yaitu 2.186 (99,1%) dari China, 18 (0,8%) dari Amerika Serikat dan 1
(0,1%) dari Iran. Sebagian besar sampel memiliki jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.254 anak
(56,9%) dan perempuan 951 anak (43,1%). Secara statistik tidak ada perbedaan yang signifikan
dalam jumlah pasien antara laki-laki dan perempuan. Waktu rata-rata mulai dari tumbulnya gejala
sampai penetapan diagnosis Covid-19 adalah 2 hari (kisaran 0 – 42 hari). Sebagian besar kasus
didiagnosis pada minggu pertama. Bayi dan anak ini diduga tertular melalui persalinan dari ibu
dengan Covid-19 sebanyak 6 bayi (0,3%) dan kontak langsung dengan anggota keluarga yang
memiliki riwayat pergi ke daerah epidemik Covid-19 sebanyak 2.199 anak (997%).14,15,16,17,18,19,20
Tingkat keparahan penyakit Covid-19 pada bayi dan anak ditentukan berdasarkan gejala
klinis, hasil laboratorium, rontgen dada sehingga dapat dikategorikan dalam lima kriteria
diagnostik berikut ini: 1) Asimtomatik yaitu tanpa gejala dan tanda klinis apapun serta hasil
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 57
rontgen dada normal, tetapi hasil tes RT-PCR (Reverse-Transcriptase Polymerase Chain
Reaction) positif. 2) Ringan yaitu adanya gejala saluran pernapasan atas seperti hidung tersumbat,
sakit tenggorokan dan demam, kelelahan, mialgia, flu, batuk, hasil rontgen dada normal serta tes
RT-PCR positif untuk SARS-CoV-2). 3) Sedang yaitu disertai pneumonia, gejala seperti demam,
batuk, kelelahan, sakit kepala, mialgia, hasil CT scan dada menunjukkan lesi paru dan tes RT-PCR
positif untuk SARS-CoV-2. 4) Berat yaitu gejala awal pernapasan seperti batuk, demam bisa
disertai diare. Berlangsung sekitar 1 minggu disertai sesak napas hingga sianosis sentral. 5) Kritis
yaitu kondisi pernapasan yang cepat berkembang menjadi ARDS (Acute Respiratory Distress
Syndrom) atau sindrom gangguan pernapasan akut ditandai dengan apas cepat (≥70 napas per menit
untuk bayi berusia <1 tahun; ≥50 napas per menit untuk anak usia> 1 tahun), gagal napas dan
mungkin juga mengalami syok, ensefalopati, gagal jantung, disfungsi koagulasi dan cedera ginjal
akut, kehilangan kesadaran, kejang hingga koma.12, 13, 14
Berdasarkan tujuh artikel penelitian, dari 2.205 sampel terdapat pembagian kriteria
diagnostik pada bayi dan anak. Kriteria asimtomatik berjumlah 2.026 anak (92%), ringan 159 anak
(7,2%) dan sedang 20 anak (0,8%). Dilaporkan seorang anak laki-laki berusia 14 tahun meninggal
karena Covid-19, tetapi tidak ada informasi yang diberikan mengenai riwayat penyakit mendasar
dari kematiannya. 14,15,16,17,18,19,20
Dari semua artikel dijelaskan bahwa usia bayi dan anak memiliki
gejala lebih ringan dibandingkan dengan gejala pada usia dewasa dan penyebab pastinya belum
diketahui. Tetapi, penyakit mendasar atau bawaan serta penyerta menjadi dugaan kuat keparahan
penyakit Covid-19 ini. Sehingga, hal ini menunjukkan bahwa angka kematian pada bayi dan anak
sangat rendah akibat Covid-19.
Tabel 1.Karakteristik Bayi dan Anak dengan Covid-19
Studi Jenis
Kelamin Jumlah sampel
Kasus Onset Kriteria diagnostik
Gejala klinis Jenis penelitian
Keluaran
Dong et al (2020)
China
Laki-laki 56,6%
Perempuan
44,4%
2.134 Berada di daerah epidemik
Covid-19
2 hari (antara
0-42
hari)
Asimtomatik 4,4%; Ringan
50,9%, sedang
38,8%
Demam, kelelahan,
gangguan
pernapasan
Studi kohort Sembuh: 2.142
Meninggal: 1
Qiu et al (2019)
China
Laki-laki 63,9%
Perempuan
36,1%
36 Kontak dengan keluarga dengan
Covid-19
14 hari Ringan 47,2%; sedang 52,8&
Batuk kering, gangguan
pernapasan ,
diare, muntah,
demam, sakit kepala, sakit
tenggorokan
Studi kohort Sembuh: 36
Aghdam et
al (2020) Iran
Laki-laki
100%
1 Lahir dari ibu
dengan Covid-19
15 hari Ringan 100% Demam, lesu,
gangguan pernapasan
Laporan
kasus
Sembuh: 1
Zhang et al
(2020)
China
Laki-laki
75%
perempuan 25%
4 Lahir dari ibu
dengan Covid-
19
28 hari Asimtomatik
25%; ringan
50%; sedang 25%
Demam,
gangguan
pernapasan, batuk
Studi
retrospektif
Sembuh: 4
Mithal et al
(2020)
Amerika Serikat
Laki-
laki38,9%
Perempuan 61,1%
18 Berada di
daerah epidemik
Covid-19
1 – 90
hari
Asimtomatik
10%
Ringan 90%
Demam, batuk,
diare, muntah,
flu, gangguan pernapasan,
rewel, tidak
napsu makan menurun
Laporan
kasus
Sembuh: 18
Wang et al
(2019)
China
Laki-laki
100%
1 Lahir dari ibu
dengan Covid-
19
36 jam Asimtomatik
100%
Asimtomatik Laporan
kasus
Sembuh: 1
Ji et al
(2020)
China
Laki-laki
100%
2 Kontak dengan
keluarga dari
daerah epidemik
Covid-19
1 hari Ringan 100% Demam, batuk Studi
retrospektif
Sembuh: 1
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 58
PEMBAHASAN
Penelitian ini menganalisis tujuh artikel jurnal mengenai gejala klinis Covid-19 pada bayi
dan anak. Gejala klinis Covid-19 pada bayi dan anak sebagian besar asimtomatik dan sisanya
hanya timbul gejala ringan sampai sedang. Tidak adanya gejala atau asimtomatik menyebabkan
penyakit Covid-19 susah untuk terdiagnosis sehingga hanya sekitar 86% dari penyakit Covid-19 di
China dapat terdiagnosis lebih awal.21
Hal ini menimbulkan kekhawatiran orang tua pada bayi dan
anaknya yang asimtomatik dan ternyata positif Covid-19, sehingga bisa menularkan penyakit ini
kepada orang dewasa disekitarnya. Menurut penelitian, kelompok usia bayi dan anak
mengakibatkan 2% kenaikan kasus Covid-19 di China, 1,2% di Italia dan 5% di Amerika
Serikat.22,23,24
Menurut penelitian, penyebab tingkat keparahan Covid-19 sangat dipengaruhi oleh penyakit
penyerta atau bawaan dari host itu sendiri. Adanya penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi,
penyakit pernapasan akut dan penyakit jantung merupakan risiko meningkatnya keparahan Covid-
19 pada orang dewasa. Sebanyak 67,2% orang yang meninggal karena Covid-19 diketahui
memiliki penyakit penyerta.25
Dalam penelitian ini, tidak ditemukan laporan atas penyakit penyerta
pada bayi dan anak yang bisa meningkatkan keparahan penyakit Covid-19. Gejala klinis pada bayi
dan anak yang dilaporkan adalah demam, batuk, kelelahan, gangguan pernapasan dan gangguan
pencernaan. Gejala klinis yang paling umum adalah demam dan batuk.
Gold standar untuk pemeriksaan Covid-19 saat ini adalah dengan pemeriksaan RT-PCR dari
RNA (Ribonucleic Acid) dari virus Covid-19. Sehingga, gejala klinis dan riwayat paparan dari
orang atau daerah epidemik Covid-19 memiliki nilai yang tinggi dalam penentuan diagnostik
Covid-19 pada bayi dan anak. Hasil pemeriksaan CT scan dada pada bayi dan anak tidak dapat
mendeteksi secara pasti tingkat keparahan penyakit ini.26,27
Penularan Covid-19 pada bayi dan anak terjadi karena persalinan dari ibu dengan Covid-19
dan kontak langsung dengan anggota keluarga yang terinfeksi Covid-19.28,29
Umumnya penyakit ini
terdiagnosis setelah 2 hari pada bayi dan anak yang terpapar Covid-19 dari orang dewasa. Tidak
ada penelitian yang menyebutkan adanya perbedaan jenis kelamin pada bayi dan anak dengan jenis
kelamin laki-laki dan perempuan.14,30
Selain itu, penularan intrauterin vertikal dari ibu hamil ke
bayi baru lahir belum pernah dilaporkan. Menurut penelitian, sampel diambil dari darah tali pusat
dan plasenta ibu hamil dengan COVID-19 dan memiliki hasil negative Covid-19. Satu penelitian
melaporkan bahwa 30 bayi baru lahir dari ibu yang terinfeksi COVID-19 memiliki hasil tes negatif.
Dijelaskan pula bahwa semua bayi dengan ibu positif Covid-19 akan dilahirkan dengan cara
operasi Caesar.31,32
Hasil penelitian saat ini tetap menyarankan ibu dengan Covid-19 untuk tetap
menyusui bayinya. Hal ini diakibatkan karena masih kurangnya penelitian tentang keberadaan virus
Covid-19 pada ASI.
KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyakit Covid-19 pada bayi dan anak sebagian
besar bersifat asimtomatik dan ringan. Gejala klinis yang umum ditemui adalah demam dan batuk.
Sedikitnya penyakit Covid-19 yang berkembang menjadi berat disebabkan karena pada bayi dan
anak tidak ditemukan penyakit penyerta seperti pada orang dewasa. Sebaiknya orang tua lebih
memperhatikan kondisi kesehatan bayi dan anak dengan atau tanpa gejala klinis Covid-19. Hal ini
dilakukan jika bayi dan anak atau anggota keluarga lainnya terpapar atau telah berkunjung ke aerah
epidemik Covid-19.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 59
DAFTAR PUSTAKA
1. MacIntyre CR. Global spread of COVID-19 and pandemic potential. Global Biosecurity.
2020;1(3). 2. Yee J, Unger L, Zadravecz F, Cariello P, Seibert A, Johnson MA, et al. Novel coronavirus
2019 (COVID-19): Emergence and implications for emergency care. Journal of the American
College of Emergency Physicians Open. 2020.1-7. 3. Cucinotta D, Vanelli M. WHO Declares COVID-19 a Pandemic. Acta bio-medica: Atenei
Parmensis. 2020;91(1):157-160. 4. Sohrabi C, Alsafi Z, O‘Neill N, Khan M, Kerwan A, Al-Jabir A, et al. World Health
Organization declares global emergency: A review of the 2019 novel coronavirus (COVID19).
International Journal of Surgery. 2020; 76:71-76.
5. Shalish W, Lakshminrusimha S, Manzoni P, Keszler M, Guilherme M. Sant‘Anna. Covid-19
and Neonatal Respiratory Care: Current Evidence and Practical Approach. American Journal of
Perinatology. 2020. DOI https://doi.org/ 10.1055/s-0040-1710522.
6. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. A novel coronavirus from patients with
pneumonia in China, 2019. New England Journal of Medicine. 2020; 382:727-733.
7. Hui DS, I Azhar E, Madani TA, Ntoumi F, Kock R, Dar O, et al. The continuing 2019-nCoV
epidemic threat of novel coronaviruses to global health–The latest 2019 novel coronavirus
outbreak in Wuhan, China. International Journal of Infectious Diseases. 2020;91:264-266.
8. Lipsitch M, Swerdlow DL, Finelli L. Defining the epidemiology of Covid-19–studies needed.
New England Journal of Medicine. 2020; 382:1194-1196.
9. Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al. Clinical course and risk factors for mortality
of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. The Lancet.
2020;395(10229): 1054-1062.
10. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease
2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese
Center for Disease Control and Prevention. JAMA. 2020;323(13):1239–1242.
11. Lu Q, Shi Y. Coronavirus disease (COVID-19) and neonate: what neonatologist needs to know.
J Med Virol. 2020. DOI: 10.1002/jmv.25740
12. Dong Y, Mo Xi, Hu Yabin, Qi Xin, Jiang Fang, Jiang Z, Shilu Tong. Epidemiological
Characteristics of 2134 Pediatrics Patients With 2019 Coronavirus Disease in China. American
Academi of Pediatrics. 2020.
13. Zhou D, Zhang P, Bao C, Zhang Y, Zhu N. Emerging Understanding of Etiology and
Epidemiology of the Novel Coronavirus (COVID-19) infection in Wuhan, China. Preprints
2020, 2020020283.
14. Dong Y, Mo X, Hu Y, Qi X, Jiang F, Jiang Z, et al. Epidemiological characteristics of 2143
pediatric patients with 2019 coronavirus disease in China. Pediatrics. 2020.
15. Qiu H, Wu J, Hong L, Luo Y, Song Q, Chen D. Clinical and Epidemiological Features of 36
Children with coronavirus Disease 2019 (Covid-19) in Zheajiang, China: an observational
cohort study. Lancet Infect Dis 2020;20: 689-96
16. Aghdam KM, Jafari N, Eftekhari K. Novel Coronavirus in a 15-Day-Old neonate with clinical
sign of sepsis, a case report. Society for Scandinavian Journal of Infectious Diseases. 2020;
VOL 0, No. ), 1-3.
17. Zhang Z-J, Yu X-J, Fu T, et al. Novel Coronavirus Infection in Newborn Babies Under 28
Days in China. Eur Respir J 2020; in press.
18. Mithal LB, Machut KZ, Muller WJ, Kociolek LK. Sars-Cov-2 Infection in Infant Less than 90
Days Old. The journal of pediatrics 2020;224:150-2.
19. Wang S, Guo L, Chen L, Liu W, Cao Y, Zhang J, et al. A Case Report of Neonatal Covid-19
Infection in China. Oxford University Press for the Infectious Diseases Society of America.
2020
20. Ji NL, Chao S, Wang YJ, Li XJ, Mu XD, Lin MG, et al. Clinical Feature of Pediatric Patients
with Covid-19: a report of two family cluster cases. World Journal of Pediatrics. 2020.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 60
21. Liu W, Tao Z-W, Lei W, Ming-Li Y, Kui L, Ling Z, et al. Analysis of factors associated with
disease outcomes in hospitalized patients with 2019 novel coronavirus disease. Chinese
Medical Journal. 2020.
22. Jung H, Kim J, Jeong S. Factors affected with posttraumatic stress in nurses involved in direct
care for Middle East respiratory syndrome patients. Health and Social Welfare Review.
2016;26(4):488-507.
23. Liu Z, Han B, Jiang R, Huang Y, Ma C, Wen J, et al. Mental Health Status of Doctors and
Nurses During COVID-19 Epidemic in China. Available at SSRN 3551329. 2020.
24. Li Z, Ge J, Yang M, Feng J, Qiao M, Jiang R, et al. Vicarious traumatization in the general
public, members, and nonmembers of medical teams aiding in COVID-19 control. Brain,
Behavior, and Immunity. 2020
25. Maunder RG, Lancee WJ, Balderson KE, Bennett JP, Borgundvaag B, Evans S, et al. Long-
term psychological and occupational effects of providing hospital healthcare during SARS
outbreak. Emerging infectious diseases. 2006;12(12):1924.
26. Park JY, Han MS, Park KU, Kim JY, Choi EH. First pediatric case of coronavirus disease 2019
in Korea. Journal of Korean Medical Science. 2020; 23;35(11):e124
27. Liu K, Chen Y, Lin R, et al. Clinical features of COVID‐19 in elderly patients: a comparison
with young and middle‐aged patients. J Infect. 2020;80(6):e14‐e18. 10.1016/j.jinf.2020.03.005
28. Cui Y, Tian M, Huang D, Wang X, Huang Y, Fan L, et al. A 55-Day-Old Female Infant
infected with COVID 19: pre senting with pneumonia, liver injury, and heart damage. The
Journal of infectious diseases. 2020; jiaa113.
29. Ji L-N, Chao S, Wang Y-J, Li X-J, Mu X-D, Lin M-G, et al. Clinical features of pediatric
patients with COVID-19: a report of two family cluster cases. World Journal of Pediatrics.
2020:1-4
30. Xing Y-H, Ni W, Wu Q, Li W-J, Li G-J, Wang W-D, et al. Prolonged Viral Shedding in Feces
of Pediatric Patients with Coronavirus Disease 2019. Journal of Microbiology, Immunology
and Infection. 2020.
31. Liu W, Tao Z-W, Lei W, Ming-Li Y, Kui L, Ling Z, et al. Analysis of factors associated with
disease outcomes in hospitalized patients with 2019 novel coronavirus disease. Chinese
Medical Journal. 2020. 41. Huang L, rong Liu H. Emotional responses and coping strategies of
nurses and nursing college students during COVID-19 outbreak. medRxiv.
2020.03.05.20031898.
32. Kim Y. Nurses‘ experiences of care for patients with Middle East respiratory syndrome-
coronavirus in South Korea. American journal of infection control. 2018;46(7):781-787.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 61
GAMBARAN PENERAPAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
PADA STAKEHOLDER DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KECAMATAN
PENJARINGAN JAKARTA UTARA TAHUN 2019
Mayumi Nitami,
1* Decy Situngkir,
2
1Dosen Program Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul
2 Program Studi Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul
*Corresponding email: [email protected],
DESCRIPTION OF THE IMPLEMENTATION OF COMMUNITY BASED TOTAL
SANITATION (CBTS) AT STAKEHOLDERS IN THE WORKING AREA OF PUSKESMAS,
KECAMATAN PENJARINGAN, NORTH JAKARTA IN 2019
ABSTRACT
Long-term, this research wants to know the profile of community-based total sanitation conditions, create
learning modules on community-based total sanitation (CBTS), and provide recommendations for improving
community-based total sanitation conditions among stakeholders so that it can improve health status in all
working areas of the Puskesmas, Penjaringan District, North Jakarta. Specific targets to be achieved in this
study are to identify the profile of a community-based total sanitation program, knowing the form of CBTS
implementation for each stakeholder in accordance with their respective roles and responsibilities. The
method that will be used to achieve long-term goals is to use qualitative study analysts. The first stage is to
know the description of community-based total sanitation in the work area of the Puskesmas, Penjaringan
District, North Jakarta by using interview guidelines and document review and observing community-based
total sanitation conditions and the second stage of this research is knowing the form of application of CBTS
for each stakeholder according to their respective roles and responsibilities -Each. The results in this study
are that there are still many CBTS targets that have not been achieved and there is still a lack of stakeholder
participation in achieving the desired targets. The networking community still needs motivation and support
from various parties in creating a good sanitation area, so it needs support from various relevant
stakeholders, especially community apparatus themselves to be more focused and more focused on running
CBTS.
Keyword: CBTS, Stakeholder, sanitation, programme
ABSTRAK
Jangka panjang penelitian ini ingin mengetahui profil kondisi sanitasi total berbasis masyarakat, membuat
modul pembelajaran mengenai sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), serta memberikan rekomendasi
dalam meningkatan kondisi sanitasi total berbasis masyarakat dikalangan stakeholder sehingga dapat
meningkatkan derajat kesehatan di seluruh wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
Target Khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi profil program sanitasi
total berbasis masyarakat, mengetahui bentuk penerapan STBM setiap stakeholder sesuai dengan peran dan
tanggungjawabnya masing-masing. Metode yang akan di pakai Untuk Mencapai Tujuan Jangka Panjanng
menggunakan analisStudi Kualitatif. Tahap Pertama adalah mengetahui gambaran sanitasi total berbasis
masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan menggunakan
pedoman wawancara dan telaah dokumenserta mengobservasi kondisi sanitasi total berbasis masyarakat dan
Tahap Kedua dari penelitian ini adalah mengetahui bentuk penerapan STBM setiap stakeholder sesuai
dengan peran dan tanggungjawabnya masing-masing. Hasil dalam penelitian ini adalah masih banyak target
STBM yang belum tercapai dan masih kurang keikutsertaan stakeholder dalam mencapai target yang
diinginkan. Masyarakat penjaringan masih membutuhkan motovasi dan dukungan dari berbagai pihak dalam
menciptakan daerah sanitasi yang baik, sehingga perlunya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan
terkait, khususnya perangkat masyarakat sendiri untuk lebih dan fokus dalam menjalakan STBM.
Kata Kunci: STBM, Stakeholder, sanitasi, program
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 62
PENDAHULUAN
Pembangunan kesehatan memiliki tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat setiap orang dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya, sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia produktif baik secara
sosial maupun ekonomis (Kemenkes, 2015). Salah satu permasalahan yang mendominasi dalam
pembanganan kesehatan adalah masalah sanitasi. Banyak tantangan yang dilami oleh Indonesia
dalam meningkatkan sanitasi antara lain tantang sosial, tantangan budaya dan perilaku masyarakat
yang masih terbiasa membuang air besar di sembarangan tempat, khususnya ke badan air dan
dimana mereka juga menggunakan air tersebut untuk mencuci, mandi dan kebutuhan lainnya
(Achmadi, 2008). Pemerintah harus terus berusaha mengatasi masalah sanitasi, terutama pada
penggunaan jamban sehat.
Program STBM memeliki strategi khusus meliputi tiga komponen yang saling mendukung
satu sama lainnya (Kar & Chamber, 2008). Pada tahun 2008 Kemkes RI mengeluarkan Kepmenkes
RI nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional lalu diperkuat dengan Permenkes RI
no.3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. STBM adalah pendekatan dalam
merubah perilaku hygiene dan sanitasi metode pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
Stakeholder merupakan pemangku kepentingan banyak orang yang dijelaskan oleh para ahli
sebagai kelompok atau individu yang mampu mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh sesuatu
untuk pencapaian tujuan tertentu (Wahyudi, 2008)
Prinsip dari pelaksanaan STBM adalah meningkatkan fasilitas sanitasi dasar dengan pokok
kegiatan menggali potensi dari masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri baik individu
mapun gotong royong dan mengembangkan solidaritas sosial. Kemenkes RI no.852/2008
menyebutkan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan memiliki peran dan tanggung
jawab dalam mempersiapkan masyarakat di tingkat kecamatan, pemerintah kecamatan berperan
dan bertanggung jawab dalam berkoordinasi serta memberi dukungan bagi kader pemicu STBM
dengan bekerja sama Badan Pemerintah yang lain.
Harapan pemerintah dengan pemicuan mampu merubah perilaku masyarakat untuk
memperbaiki kondisi sanitasi lingkungan dilingkungan mereka, sehingga mampu mencapai target
Open Defecation Free (ODF) pada suatu wilayah (Kemenkes RI,2012). Suatu desa menjadi ODF
atau Bebas BABs jika 100% penduduka desa tersebut mempunyai akses BAB di jamban sehat dan
tidak membuang sembarangan. Menurut sekretaris STBM Nasional, capaian ODF di Indonesia
secara nasional hingga tahun 2014 baru 44,17% dari semua daerah yang melaksanakan STBM ke
masyarakat (Kemenkes RI, 2014). Wilayah kerja puskesmas kecamatan penjaringan, jakarta utara
memiliki 6 Puskesmas kelurahan, dimana dari 6 Puskesmas tersebut baru 1 Puskesmas kelurahan
yang mencapai indikator 100% dengan status deklarasi. Hal ini menyebabkan peneliti ingin
mengetahui seperti apa bentuk implementasi program STBM dan peran Stakeholder STBM dalam
menjalankan program STBM ke masyarakat.
Penelitian ini memiliki tujuan yang nantinya akan dapat bermanfaat bagi pengembangan dan
peningkatan kualiatas hidup masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang tinggi. Agar dapat
mengetahui permasalahan STBM dan kemudian akan dihubungkan terhadap permasalahan
program STBM yang dilaksanakan. Agar dapat meningkatkan keberhasilan program STBM di
Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 2019.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 63
METODE
Penelitian ini akan dilaksanakan wilayah kerja Puskesmas Penjaringan, Jakarta Utara.
Variabel penelitian ini adalah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Peran Stakeholder.
Metode penelitian ini menggunakan studi kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif yang bersifat observasional, menggunakan desain studi cross sectional. Teknik
pengumpulan data menggunakan total sampling dimana responden penelitian ini adalah seluruh
stakeholder yang terlibat dalam program STBM di wilayah kerja Puskesmas Penjaringan, Jakarta
Utara.
HASIL
Hasil penilitian ini mendapatkan gambaran pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat
(STBM) bahwa dari 5 pilar STBM masih banyak yang belum terselesaikan, terutama untuk
menciptakan Stop BABs masih sangat sulit dilakukan, terkait dengan fasilitas, sarana dan prasaran
serta dukungan-dukungan dari beberapa pihak masih sangat minim sekali.
Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara mendalam kepada pihak puskesmas yang pemegang
program STBM:
―masih sangat sulit untuk mencapai target STBM, soalnya wilayah sini kan juga
kemampuan finansialny kurang, trus sarana prasarana juga masih belum mendukung. apalagi
masyarakatnya, hmmm... susah banget buat diberdayakan, mereka fikir ini kerjanya kita, bukan
mereka... gtu...‖
berdasarkan tokoh masyarakat kecamatan penjaringan:
―masyarakat disini tuh.. agak susah diajak buat gotong royong gtu... mereka tau
sebenarnya manfaatnya buat mereka, tapi karna harus mengeluarkan biaya mereka jadi malas
gtu, yaa soalnya kan mereka itu rata-rata penghasilannya kecil, cukup buat makan saja, anak-
anak aja banyak yang gak sekolah....‖
berdasarkan masyarakat:
― yaaa gimana yaa mba... kita sih maunya pemerintah ngerti gitu sama keadaan kita, yaa
kalau pun mau sum-sum kita yaaaa... Cuma sanggup berapa, kadang kami juga pengen mba
bisa lebih sehat, tapi keadaan mba...‖
Hal ini sangat mempengaruhi pencapaian target dari STBM itu sendiri. Keaktifan dari
stakeholder yang harusnya berperan, masih jarang terlaksana dalam memberdayakan masyarakat
secara langsung turun ke masyarakat, mereka hanya melaksanakan perencanaan dan evaluasi tanpa
ikut serta turun ke lapangan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut.
Menurut masyarakat:
―ada sih mba... kadang yang ikut pak RT, karang taruna, terus kayaknya ada dari
pemerintahan gitu yang ikut, kadang juga ada beberapa warga yang diundang... disana kita
rapat, rapatnya yaaa... bahasnya tentang masalah-masalah kesehatan yang ada di wilayah sini,
terus mau diapain biar baik lagi..., tapi udah gtu ajaa... klo ke tempat kita mah jarang, paling
keliling doang, ga ada rembuk-rembukan gitu...‖
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 64
Menurut Petugas Puskesmas:
―sulitnya waktu untuk mengumpulkan menjadi salah satu kendala dari stakeholder untuk
bertemu, dan mereka juga kadang diwakilkan oleh orang lain juga, jadinya yaaa susah... jadi
yang udah-udah tu inisiatif puskesmas dan kerjasama dengan warga yang emang beneran
peduli, jadi ada beberapa warga yang mau..‖
Selain itu juga, ada beberapa dari stakeholder yang tidak mengetahui dan kurang mengerti
dengan perannya sebagai salah satu pemangku kepentingan terkait STBM ini, sehingga untuk
merencanakan dan melaksanakan program menjadi lebih sulit. Menurut merekan lebih baik
program dilakukan per lingkup kecil, sehingga lebih fokus dan efektif.
Berikut hasil wawncara dengan Pak RT dari RT 2:
―.......saya gatau mba saya harus ngapain, ikut-ikut rapat aja, tapi ga ada pembagian tugas,
soalnya kan yang datang banyak,.............. harusnya mungkin bisa lebih baik jika dilingkup kecil
rapatnya, biar pokus gitu ke orang-orangnya...‖
Jadi, pelaksanaan STBM dan Peran stakeholder di wilayah kerja puskesmas Penjaringan
masih banyak kendala yang harus diselesaikan, terutama pada pemahaman masyarakat terkait
pelaksanaan STBM yang ada dimasyarakat. 5 Pilar STBM yang dilaksnakan di kecamtan
Penjaringan, hanya Pengelolaan air minum dan makanan yang baik, selebihnya masih banyak pilar
yang belum diatasi, dilihat dari hasil observasi wilayah tersebut sangat sulit untuk mencapai kelima
pilar tersebut.
Selain itu bentuk motivasi yang ada dalam pelaksanaan STBM di Penjaringan hanya pada
hasil saja, tidak berdasarkan proses Karen kurangnya pemahaman dan pendekatan yang dilakukan
kepada masyarakat, sehingga sebagian masyarakat pun tidak terlalu peduli ada atau tidaknya
STBM diwilayah mereka.
Masyarakat:
―….. ya itu tadi mba, saya karna ndak ada duitnya, saya ga bis apa-apa gtu, kalau emang mau
dilakukan perbaikan sarana disini yaaa ayaook aja.. paling bantu tenaga, kalo biaya ga
sanggup..‖
Tokoh Masyarakat:
―…..sebenarnya minat mereka ada mba, mereka ingin sehat, gamau juga hidup kayak gini
dilingkungan kumuh, tapi yaaa itu balik lagi, mereka dari awal udah mikir biaya, jadinya
yaudahlah gini aja juga udah cukup….. banyak yang seperti itu…..‖
Pelaksanaan STBM di wilayah kerja Puskesmas penjaringan masih belum efektif, hal ini
dapat terlihat masih belum deklarasi dibeberapa wilayah terkait stop BABs. Hal ini berkaitan
dengan jarak instalasi pembuangan tinja yang belum memenuhi syarat mulai dari jarak, jenis
pembuangan namun yg paling sulit adalah jarak dari sumber air. Kondisi lingkungan dengan
jumlah hunian padat, sempit, dan kumuh di wilayah seperti RW 12 dan 13 Penjaringan tidak
memungkinkan warga membangun tangki septik dengan jarak minimal 10 m dari sumur gali.
Begitu juga dengan pilar lainnya, dilihat berdasarkan hasil observasi yang melihat kondisi
lingkungan yang sangat sulit untuk dilakukannya STBM khususnya wilayah pesisir pantai.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 65
PEMBAHASAN
Pelaksanaan STBM diwilayah ini masih kurang peranan dari stakeholder yang ada.
Stakeholder yang harusnya bisa memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kesdaran, justru
sangat kesulitan dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab tersebut,karena kurangnya
pemahaman mereka terkait tugas yang harus dikerjakan. Edukasi atau pendidikan kesehatan
dianggap sebagai komponen promosi kesehatan (Dee Leeuw, 1989). Edukasi dalam suatu kegiatan
bertujuan meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, dan mengarahkan perilaku yang diinginkan
oleh kegiatan tersebut (Heri D.J Maulana, 2007). Berdasarkan teori tersebut maka perlu dilakukan
pendidikan kesehatan untuk masyarakat agar mudah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi
dalam menyelesaikan masalah sanitasi yang berada di lingkungan, membangun kapasitas
kelompok, kesadaran dan meningkatkan kebutuhan mereka akan STBM ini, serta opsional
teknologi yang bisa digunakan dalam melengkapi fasilitas STBM yang dibutuhkan. Hal ini
diperlukan pendampingan kepada masyarakat untuk memotivasi, menurut Pane (2009) dari hasil
penelitiannya kegiatan pendampingan program yang kurang baik pasca pemicuan dilakukan dapat
menyebabkan masyarakat kembali berperilaku buruk karna tidak adanya monitoring. Berdasarkan
penelitian terkait, untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat dilakukan pemantauan dan
monitoring berkala setiap 1 dan 2 minggu sekali setiap bulannya, yang dipantau adalah komitmen
masyarakat (Sitra,dkk, 2019).
Pelaksanaan STBM pokok kegiatannya terdiri dari advokasi, pengembangan kapasitas
lembaga dan peningkatan kemitraan antar stakeholder. Pokok kegiatan ini harusnya direncakan
dengan baik, ditetapkan berdasarkan keputusan bersama, dan dipecahkan secara bersama, sesuai
dengan metodenya kegiatan yang berbasis masyarakat. Sehingga masyarakat sendiri yang
menganalisis masalahnya, mencari solusinya, merencanakan kegiatannya hingga monitoring dan
evaluasi. Berdasarkan penelitian Fatonah (2016), factor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi
dalam pelaksanaan STBM adalah secara internal stakeholder yang wajib ikut terlibat dalam
program STBM ini adalah seperti pemerintah daerah, perangkat desa dan fasilitator (petugas
kesehatan). Jadi, untuk meningkatkan keefektifitasan pelaksanaan STBM harus terlibat stakeholder
terkait, untuk meyakinkan kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran dalam pelaksanaan
STBM ini. Begitu juga yang dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Teknis STBM (2012) bahwa
keterlibatan pemangku kepentingan harus mendukung upaya pemerintah berupa pembiayaan,
advokasi dan bantuan teknis. Advokasi merupakan upaya yang sangat diperlukan untuk
mengingatkan dan mendesak negara dan pemerintah untuk berperilaku konsisten dan
bertanggungjawab dalam melindungi dan mensejahterakan warganya. Hal ini berarti para pelaksana
advokasi tanggung jawab untuk ikut berperanserta menjalankan fungsi pemerintahan dan negara
(zulyadi, 2014).
Kemitraan yang dimaksud dalam program STBM adalah salah satu upaya untuk mendukung
penyelenggaraan STBM, seperti melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring
kerja, dan kemitraan dengan para pamangku kepentingan (Kemenkes RI, 2014). Kondisi Jakarta
yang sangat padat, dan masih banyak terdapat wilayah-wilayah slum area menyebabkan pemikiran
pesimis untuk melakukan pendekatan STBM oleh mitra setempat untuk melaksanakan kegiatan ini
kepada masyarakat. Kenyataannya, STBM yang dibentuk dari masyarakat merupakan kunci sukses
dalam gerakan ini. Selain itu, jumlah sanitarian yang masih belum mencukupi untuk wilayah
Penjaringan juga menjadi hambatan, oleh karena itu kesenjangan ini perlu diatasi dengan
peningkagtan mitra yang mampu membantu dan berkomitmen untuk hal ini. Strategi pemicuan
harus dilakukan secara individu, namun untuk konteks pemukiman padat Jakarta, strategi pemicu
juga bisa dilakukan pada kelompok.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 66
Hal ini dibuktikan selama proses verifikasi dan deklarasi STBM, kesulitan yang sering
ditumui adalah melibatkan unit terkecil wilayah dalam sistem monitoring seperti desa/kelurahan.
Startegi ini mempermudah pengelolaan STBM pada unit terkecil wilayah di tingkat RT/RW dalam
mengimplementasikan program di perkotaan.
Perlu adanya pemantauan khusus yang terencana dan sistematis sebagai bentuk kepedulian
pemerintah, karena pemantauan sangat berperan penting dalam pelaksanaan suatu program,
menurut Supriyanto dan Damayanti (2007) pemantauan mampu menjadi kegiatan evaluasi formatif
pada tahap pelaksanaan program untuk mengubah atau memperbaiki program. Evaluasi dapat
dilaksanakan jika ada dokumentasi lengkap dan rutin, sehingga dapat melihat perkembangan
program, hal ini dapat dilakukan dengan adanya pencatatan dan pelaporan. Sesuai dengan teori
pencatatan memiliki manfaat dalam memberi informasi tentang keadaan masalah, memberikan
bukti dari suatu kegiatan, menjadi bahan proses belajar dan penelitian, serta sebagai
pertanggungjawaban untuk bahan pembuatan laporan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi,
bukti hukum, alat komunikasi dalam menceritakan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan
(Mubarak, 2012).
KESIMPULAN DAN SARAN
Strategi dalam upaya meningkatkan indicator STBM ini masih perlu kerja keras bersama
dalam melibatkan stakeholder dengan masyarakat, memberikan motivasi yang dapat memicu dan
meningkatkan kesadaran untuk melaksanakan STBM ini. Adapun saran yang bias
direkomendasikan adalah menyusun ulang strategi pencapaian program secara bersama dengan
melibatkan masyarakat secara optimal.
DAFTAR PUSTAKA
1. Achmadi, Umar F. 2008. Horison Baru, Kesehatan Masyarakat Di Indonesia. Jakarta:
Rineka Cipta.
2. Adisasmito, W, 2008, Sistem Kesehatan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
3. Boalemo Gorontalo, Tesis, Universitas Diponegoro.
4. Bryan, dkk, 1987.Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. LP3ES:Jakarta
5. Chandra, B, 2007. Pengantar kesehatan lingkungan.Kedokteran EGC: Jakarta
6. Deak, A., 2008, Taking community-led total sanitation to scale: movement,
7. Dee Leeuw. (1989). The same revolution : Health Promotion backgrounds, scope,
prospects. Assen / Maastrich: van Gorcum.
8. Ditjen PP dan PL, 2013, Road Map Percepatan Program STBM 2013-2015,
9. Heri D.J Maulana. (2007). Promosi Kesehatan . Jakarta: Kedokteran EGC.
10. Kar, K dan R.Chambers. 2008. Handbook on Community-Led total Sanitation. Plan UK:
London
11. Kementerian Kesehatan RI. 2014. Permenkes RI No. 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat. Jakarta
12. KemenKes, 2008. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
852/Menkes/SK/IX/2008 Strategi nasional sanitasi total berbasis masyarakat. Jakarta:
Kemenkes RI.
13. Kementerian Kesehatan. 2015. Permenkes No. 33 Th 2015 Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan SDM Kesehatan.Jakarta: Kemenkes RI
14. Kementerian Kesehatan. 2012. Pedoman Pelaksanaan Teknis STBM.Jakarta:Kemenkes RI
15. Millenium Challenge Account-Indonesia.2015. Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat. Jakarta: MCA-Indonesia
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 67
16. Mubarak, N. C. (2007). Promosi Kesehatan : Sebuah Pengantar Proses Belajar Mengajar
Dalam Pendidikan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
17. Pane, E, 2009. Pengaruh Perilaku Keluarga Terhadap Penggunaan Jamban. Jurnal
kesehatan Masyarakat Nasional. Hal. 229
18. Rosensweig, Fred dan Derko Kopitopoulos, 2010. Building the Capacity of Local
Goverment to Scale Up Community-Led Total Sanitation and Sanitation Marketing in
Rural Areas. World Bank: Water Sanitastion Program
19. Supriyanto, S, Damayanti, NA. 2007. Perencanaan dan Evaluasi. Airlangga University
Press. Surabaya
20. Surotinojo, Ibrahim, 2009. Partisipasi Masyarakat dalam Program Sanitasi oleh Masyarakat
(Sanimas) di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Gorontalo, Tesis,
Universitas Diponegoro.
21. Wahyudi, Isa, dan Busyra Azheri, 2008. Corporate Social Responsibility: Prinsip,
Pengaturan dan Implementasi. Malang: In-Trans Publishing.
22. WHO/UNICEF, 2015. Progress on sanitation and drinking – water. WHO: Geneva
23. Zahrina, A. F., Suryadi, & Suwondo. (2015). Implementasi Program Gerakan Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan. Jurnal Administrasi Publik,
3(11), 1832-1836.
24. Zastrow, Charles. 2008. Introducion to Social Work and Socia Welfare. Empowering
People. Thomson Peolpe. Thomson Books, Belmont-US.
25. Zulyadi, T. (2014). Advokasi Sosial. Jurnal Al-Bayan, 21(30), 63-66.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 68
DISTRIBUSI BALITA THIRD HAND SMOKE DI KOTA PALEMBANG
Amrina Rosyada,
1* Dini Arista Putri,
2 Nurmalia Ermi
3
1,3Bagian Epidemiologi dan Biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya
2Bagian Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya
Jl. Palembang Prabumulih KM.32, Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan
Corresponding email : [email protected]
DISTRIBUTION OF THIRD HAND SMOKE CHILDREN IN PALEMBANG
ABSTRACT
Third hand smoke is a term used for people who are exposed to cigarette smoke residues that stick to items
around the former smoking area. In toddlers, third hand smoke can endanger their health because toddlers
have lower body resistance. In the long term, toddlers with third hand smoke can experience serious health
problems and even cancer. Public knowledge regarding third hand smoke is still very low. The purpose of
this study was to determine the proportion of toddlers with third hand smoke in Palembang. This study used
a cross sectional research design. The research sample was under five in the city of Palembang who had
father who smoked as many as 180 children. The sampling method using cluster random sampling. Data
analysis using univariate analysis. Based on the results of the analysis, 31.1% of children under five were in
the third hand smoke category where the father smoked in the house or did not prevent exposure to cigarette
residues after smoking. It is necessary to do public health intervention and promotion in order to prevent the
high number of children under five third hand smoke.
Keywords : Toodler, Third Hand Smoke, Smoker Father
ABSTRAK
Third hand smoke merupakan istilah yang digunakan untuk orang yang terpapar residu asap rokok yang
menempel pada barang-barang disekitar bekas tempat merokok. Pada balita, third hand smoke dapat
membahayakan kesehatan mereka karena balita memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah. Dalam jangka
panjang, balita third hand smoke dapat mengalami gangguan kesehatan berat bahkan kanker. Pengetahuan
masyarakat terkait thir hand smoke masih sangat rendah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proporsi
balita third hand smoke di kota Palembang. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional.
Sampel penelitian yaitu balita di kota Palembang yang memiliki ayah perokok sebanyak 180 balita. Metode
pengambilan sampel dengan menggunakan cluster random sampling. Analisis data menggunakan analisis
univariat. Berdasarkan hasil analisis, 31.1% balita terkategori third hand smoke dimana ayah merokok di
dalam rumah atau tidak melakukan pencegahan paparan residu rokok setiap selesai merokok. Perlu dilakukan
intervensi dan promosi kesehatan terhadap masyarakat guna pencegahan tingginya angka balita third hand
smoke.
Kata Kunci : Balita, Third hand smoke, Ayah Perokok
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 69
PENDAHULUAN
Berdasarkan laporan WHO tahun 2017, tercatat Indonesia merupakan Negara dengan jumlah
perokok terbesar di dunia dimana tercatat 76% pria diatas 15 tahun adalah perokok1. Data Riset
Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan Kementerian Kesehatan menunjukkan peningkatan
prevalensi perokok pada tahun 2007, 2010, dan 2013 berturut-turut meningkat dari 34,2%; 34,7%
dan akhirnya 36,3%. Terdapat 92 juta orang perokok pasif yang terdiri dari 43 juta di antaranya
anak-anak 11,4 juta dari anak-anak ini masih berusia balita.2
Fakta berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bahaya rokok tidak hanya dialami
bagi perokok saja namun juga orang-orang disekitar perokok yang disebut perokok pasif. Asap
sampingan yang diterima perokok pasif diketahui jauh lebih tinggi kadar senyawa kimianya
dibandingkan asap utama yang diterima perokok sendiri.3 Penelitian Aditama menyebutkan bahwa
seorang perokok pasif yang berada dalam ruangan yang penuh asap rokok selama satu jam saja
akan mengisap nitrosamin sama banyaknya dengan merokok 35 batang rokok.4
Orang tua saat ini sudah banyak mengetahui bahwa rokok berbahaya bagi anak khususnya
anak balita. Anak-anak berpotensi besar terkena paparan dampak buruk rokok dikarenakan anak-
anak memiliki massa tubuh yang lebih kecil, bernafas lebih cepat, dan memiliki ketahanan tubuh
yang lebih rendah dibandingkan dewasa.5 Namun, tidak banyak orang tua mengetahui bahwa tidak
hanya asap rokok yang berbahaya bagi anak namun residu dari asaprokok yang menempel pada
baju, badan, dan perabotan di sekitar tempat merokok apabila dijangkau oleh anak dapat terhirup
dan membahayakan kesehatannya. Fakta ini disebut dengan third hand smoke.6–8
Dampak jangka panjang pada anak, paparan residu asap rokok ini dapat menimbulkan
penyakit berbahaya seperti kanker, gangguan jantung, gangguan pada paru, bahkan diabetes
mellitus di usia dewasa.8–10
Dalam mempersiapkan generasi masa depan yang sehat dan berkualitas,
pencegahan paparan asap rokok maupun residu asap rokok perlu digalakkan dalam keluarga. Oleh
karena itu pada penelitian ini akan diidentifikasi besaran balita third hand smoke di kota Palembang
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian dengan desain studi cross-sectional. Populasi penelitian
yaitu seluruh anak balita di Kota Palembang yang memiliki ayah perokok. Penelitian di lakukan di
Kota Palembang selama Juli-September 2020. Metode pengambilan sampel menggunakan cluster
sampling terpilih 4 kecamatan dari 17 kecamatan di Kota Palembang. Berdasarkan perhitungan
sampel beda dua proporsi dan mempertimbangkan deff maka sampel penelitian ini berjumlah 180
balita. Indikator third hand smoke adalah jika balita mempunyai ayah perokok, ayah merokok di
dalam rumah, atau ayah tidak melakukan pencegahan paparan residu rokok dengan tidak berganti
baju, mencuci muka, mencuci tangan dan mandi setiap selesai merokok sebelum menggendong
atau bermain dengan anak. Analisisi data menggunakan analisis univariat untuk melihat distribusi
balita third hand smoke di kota Palembang
HASIL PENELITIAN
Penelitian dilakukan pada 4 kecamatan di kota Palembang sebagai cluster terpilih sebanyak
180 responden. Berikut hasil penelitian:
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 70
Tabel 1. Sikap Ayah terhadap Third Hand Smoke
Variabel Frekuensi Persentase
Sikap Ayah
1. Kurang Baik
2. Baik
89
91
49.4%
50.6%
Total 180 100.0%
Berdasarkan data diatas diketahui bahwa sebagai besar ayah memiliki sikap baik terhadap third
hand smoke (50.6%) seperti menghindari merokok di dalam rumah, tidak memeluk anak setelah
selesai merokok dan berganti baju serta mandi setelah merokok.
Tabel 2. Sosial Ekonomi Keluarga
Variabel Frekuensi Persentase
Sosial Ekonomi
1. Rendah
2. Tinggi
77
103
42.8%
57.2%
Total 180 100.0%
Sebagian besar responden memiliki sosial ekonomi tinggi (57.2%) yang artinya sebagian besar
responden memiliki pendidikan minimal sekolah menengah atas dan pendapatan diatas UMR Kota
Palembang
Tabel 3. Status Perokok Ayah
Variabel Frekuensi Persentase
Status Perokok
1. Berat
2. Ringan
137
43
76.1%
23.9%
Total 180 100.0%
Sebagian besar responden termasuk golongan perokok berat yaitu merokok lebih dari atau sama
dengan 12 batang rokok per hari
Tabel 4. Jenis Kelamin Balita
Variabel Frekuensi Persentase
Jenis Kelamin
1. Laki-laki
2. Perempuan
127
53
70.6%
29.4%
Total 180 100.0%
Sebagian besar anak balita yang dijadikan sasaran penelitian berjenis kelamin laki-laki (70.6%)
Tabel 5. Umur Balita
Variabel Mean Median SD Min-Max
Umur 24.3 18 17.6 1-60
Rata-rata responden anak berusia 24 bulan atau 2 tahun dengan minimal 1 bulan dan maksimal 60
bulan atau setara dengan 5 tahun
Tabel 6. Status Third Hand Smoke Balita
Variabel Frekuensi Persentase
Third Hand Smoke
1. THS
2. Tidak THS
56
124
31.1%
68.9%
Total 180 100.0%
Berdasarkan hasil penelitian terhadap kebiasaan ayah, diketahui sebanyak 31.1 % anak terindikasi
third hand smoke melalui indikator ayah merokok di dalam rumah, ayah tidak berganti baju,
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 71
mencuci tangan, mencuci muka, atau mandi setelah merokok serta ayah memiliki kebiasaan
menggendong dan mencium anak setelah selesai merokok
Tabel 7. Pertanyaan Sikap Ayah terhadap Third Hand Smoke
Variabel Frekuensi Persentase
Saya berganti baju setelah selesai merokok
1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. Setuju
4. Sangat Setuju
9
31
57
83
5.0
17.2
31.7
46.1 Saya selalu mencuci tangan setelah selesai merokok
1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. Setuju 4. Sangat setuju
6
30
29 115
3.3
16.7
16.1 63.9
Saya sering merokok di dalam rumah
1. Setuju
2. Tidak Setuju 3. Sangat tidak setuju
67
52 61
37.7
28.9 33.9
Saya merokok di kamar mandi
1. Sangat setuju
2. Setuju 3. Tidak setuju
4. Sangat tidak setuju
35
62 48
35
19.4
34.4 26.7
19.4
Saya merokok di dalam mobil
1. Sangat setuju 2. Setuju
3. Tidak setuju
4. Sangat tidak setuju
21 52
71
36
11.7 28.9
39.4
20.0
Saya menghindari menggendong bayi setelah merokok 1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. Setuju
4. Sangat setuju
105
67
1
7
58.3
37.2
0.6
3.9 Saya mandi setelah selesai merokok
1. Tidak setuju
2. Setuju
3. Sangat setuju
44
91
45
24.4
50.6
25.0
Saya langsung mandi dan berganti baju sepulang kerja sebelum
menemui anak
1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju 3. Setuju
4. Sangat setuju
7
35 51
87
3.9
19.4 28.3
48.3
Saya langsung memeluk atau mencium anak sepulang kerja
1. Sangat setuju 2. Setuju
3. Tidak setuju
4. Sangat tidak setuju
8 29
197
36
4.4 16.1
59.4
20.0
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa masih 37.7% ayah yang merokok di dalam rumah
dan 95,5% ayah masih menganggap tidak masalah menggendong bayi langsung setelah selesai
merokok. Hal ini mengindikasikan pengetahuan yang rendah dari masyarakat terhadap dampak
residu rokok yang tertinggal di baju dan perabotan rumah terhadap kesehatan anak.
PEMBAHASAN
Saat ini kesadaran masyarakat tentang bahaya asap rokok terhadap kesehatan balita dan anak
sudah mulai meningkat. Banyak keluarga muda sudah mulai menjauhkan anaknya dari asap rokok
baik dari orang lain maupun asap rokok dari anggota keluarga sendiri. Namun, masyarakat masih
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 72
belum banyak yang mengetahui bahwa tidak hanya asap rokok langsung yang berbahaya namun
residu atau sisa asap rokok yang menempel pada perabotan rumah seperti sofa, gorden, karpet serta
residu yang menempel pada baju, rambut dan muka setelah selesai merokok juga berbahaya.
Residu rokok juga dapat bertahan sangat lama di dalam ruangan walaupun jendela rumah sudah
dibuka dan dibersihkan.
Residu asap rokok masih berbahaya walaupun sudah tidak ada perokok di ruangan tersebut.
Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa residu zat nikotin yang dihasilkan perokok dapat
membentuk zat karsinogen yang disebut nitrosamine. Zat ini berpotensi menimbulkan kanker
apabila terpapar dalam waktu yang lama. Residu rokok akan menempel dalam waktu yang lama
pada baju, handphone, perabot rumah tangga, lantai, peralatan makan dan apabila tersentuh,
terhirup dan termakan dapat menyebabkan perubahan genetik, kanker, dan gangguan kesehatan
lainnya. 11–13
Third hand smoke adalah penghirup residu nikotin dan bahan kimia yang dihasilkan oleh
perokok. Seseorang dapat terpapar residu ini dengan menyentuh dan menghirup area bekas tempat
merokok walaupun sudah tidak ada perokok di ruangan tersebut. Residu ini akan bercampur
dengan polusi udara lain dan membentuk zat pemicu kanker yang bisa membahayakan orang yang
tidak merokok terutama anak- anak. Residu dari asap rokok akan menempel pada baju, furniture,
dinding, lantai, karpet, mobil walaupun asap rokok sudah hilang. Untuk menghilangkan residu ini
barang-barang harus sering dicuci dan dibersihkan. Residu asap rokok tidak dapat dihilangkan
dengan hanya membuka jendela dan menggunakan kipas angin. 6,7,13
Anak-anak berpotensi besar
terkena paparan dampak buruk rokok dikarenakan anak-anak memiliki massa tubuh yang lebih
kecil, bernafas lebih cepat, dan memiliki ketahanan tubuh yang lebih rendah dibandingkan
dewasa).5
Berdasarpakn hasil penelitian diketahui 31.1% balita termasuk third hand smoke. Angka ini
cukup tinggi dan dapat berkembang menjadi angka lebih besar. Sehingga tindakan pencegahan
perlu dilakukan untuk menghentikan paparan serta mencegah yang tidak terpapar. Edukasi terhadap
orang tua terutama ayah merupakan aspek penting untuk menekan angka balita third hand smoke.
Dari hasil pengamatan dilapangan para ayah sangat mengetahui dampak rokok terhadap anak dan
berupaya menjauhkannya namun rata-rata para ayah tidak mengetahui jika residu rokok juga
berbahaya untuk anak.
KESIMPULAN DAN SARAN
Sebanyak 70.6% responden anak berjenis kelamin laki laki dengan rentang umur 1-60 bulan.
57.2% keluarga memiliki status sosial ekonomi tinggi, 50.6% ayah memiliki sikap pencegahan
yang baik terhadap paparan rokok, 76.1% balita memiliki ayah dengan status perokok berat.
Sebanyak 31.1% anak termasuk dalam kateogri third hand smoke dimana indikatornya adalah ayah
merokok di dalam rumah dan ayah tidak melakukan pencegahan setiap selesai merokok seperti
mandi, berganti baju dan mencuci muka serta tangan. Perlu dilakukan promosi kesehatan kepada
para ayah dan ibu yang memiliki balita mengenai konsep third hand smoke, bahaya dan cara
menghindarinya.
DAFTAR PUSTAKA
1. Liputan 6. WHO: Rokok ‗Bunuh‘ 10 Orang Per Menit - Global Liputan6.com.
Liputan6.com, https://www.liputan6.com/global/read/3544429/who-rokok-bunuh-10-orang-
per-menit (2019, accessed 24 December 2019).
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 73
2. Detik Health. Terpapar Residu Asap Rokok Ayahnya, Bayi Ini Meninggal Kena Pneumonia.
Detik Health, https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2534413/terpapar-residu-asap-
rokok-ayahnya-bayi-ini-meninggal-kena-pneumonia (2014, accessed 24 December 2019).
3. Sharon, Natalie, Jian, et al. Nicotinic agonists stimulate acetylcholine release from mouse
interpeduncular nucleus: a function mediated by a different nAChR than dopamine release
from striatum. J Neurochem 2001; 77: 258–268.
4. Aditama T. Rokok dan Kesehatan. Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
5. World Health Organization. Second-hand smoke. 2014.
6. Jacob P, Benowitz NL, Destaillats H, et al. Thirdhand smoke: New evidence, challenges,
and future directions. Chem Res Toxicol 2017; 30: 270–294.
7. Matt GE, Quintana PJE, Zakarian JM, et al. When smokers quit: Exposure to nicotine and
carcinogens persists from thirdhand smoke pollution. Tob Control 2017; 26: 548–556.
8. Roberts C, Wagler G, Carr MM. Environmental Tobacco Smoke: Public Perception of
Risks of Exposing Children to Second- and Third-Hand Tobacco Smoke. J Pediatr Heal
Care 2017; 31: e7–e13.
9. Halsted C, Pew A. Third-Hand Smoke. National Center For Health Research,
http://www.center4research.org/third-hand-smoke/ (2019, accessed 24 December 2019).
10. Matt GE, Quintana PJE, Hoh E, et al. A Casino goes smoke free: A longitudinal study of
secondhand and thirdhand smoke pollution and exposure. Tob Control 2018; 27: 643–649.
11. Acuff L, Fristoe K, Hamblen J, et al. Third-Hand Smoke: Old Smoke, New Concerns.
Journal of Community Health 2016; 41: 680–687.
12. Bahl V, Jacob P, Havel C, et al. Thirdhand cigarette smoke: Factors affecting exposure and
remediation. PLoS One; 9. Epub ahead of print 6 October 2014. DOI:
10.1371/journal.pone.0108258.
13. Matt GE, Quintana PJE, Zakarian JM, et al. When smokers move out and non-smokers
move in: residential thirdhand smoke pollution and exposure. Tob Control 2011; 20: e1–e1.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 74
PENGETAHUAN, SIKAP, DAN PERILAKU 3M (MENGGUNAKAN MASKER,
MENJAGA JARAK, DAN MENCUCI TANGAN DENGAN SABUN)
MASYARAKAT INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19
Heny Lestary
*, Cahyorini, Khadijah Azhar, Sugiharti
Peneliti Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat, Badan Litbangkes, Kemenkes RI Jakarta
Jl. Percetakan Negara No. 29 Jakarta Pusat
Corresponding email : [email protected]
KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND BEHAVIOR OF 3M (USING A MASK, MAINTAINING
DISTANCE, AND WASHING HANDS WITH SOAP) INDONESIAN COMMUNITY IN THE
TIME OF THE COVID-19 PANDEMIC
ABSTRACT
The first COVID-19 cases were discovered in Indonesia on March 2, 2020. As of September 12, 2020, the
Ministry of Health recorded 214,746 confirmed cases, with 8,650 deaths, spread across 489 districts/cities in
Indonesia. The central and local governments have launched the 3M program as a means of preventing
COVID-19.The research objective was to determine the knowledge, attitudes and behavior of 3M (using
masks, maintaining distance, and washing hands with soap) in Indonesia in the face of The COVID-19
pandemic.The cross-sectional research method used a structured questionnaire sent online via whatsapp at
the end of April 2020. Respondents came from 34 provinces with the total of 1,807 with at least 15 years of
age. The proportion of knowledge about the wrong use of masks was 8.9%, the obligatory attitude to use
masks did not occur in 0.8% of respondents, the behavior of always used masks was 94.7%, where the lowest
behavior was for male respondents (92.3%), 15 – 25 years (91.2%), and junior high school education
(75.9%). Correct knowledge of maintaining distance was 92.8%, disagrement with maintaining distance is
1.6% and behavior of always maintaining distance 68.5%, where the lowest behavior was in male
respondents (63.8%), 36 – 45 years (56.5%), higher education (66.1%). The correct knowledge of washing
hands with soap was 94.9%, the right attitude was 99.6%, and the behavior of respondents who always wash
their hands with soap was 74.2%, where the lowest behavior was male respondents (69.0%), 15 – 25 years
(70.3%), junior high school education (51.7%). It was that 3M’s knowledge, attitudes, and behavior have not
been carried out thoroughly and consistently during The COVID-19 Pandemic. It is necessary to increase
3M’s knowledge, attitudes, and behavior by further promoting national and regional campaigns, presenting
agents of change, and other health promotion efforts so that the public will increase their awareness to
protect themselves, their families, and the environment.
Keywords: COVID-19, masks, maintaining distance, washing hands with soap.
ABSTRAK
Kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Hingga tanggal 12
September 2020, Kementerian Kesehatan mencatat 214.746 kasus konfirmasi, dengan 8.650 kasus
meninggal, yang tersebar di 489 kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah mencanangkan
program 3M sebagai cara pencegahan COVID-19. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengetahuan, sikap,
dan perilaku 3M (menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun) masyarakat
Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Penelitian potong lintang menggunakan kuesioner
terstruktur yang dikirimkan secara daring melalui jejaring whatsapp pada akhir April 2020. Responden
berasal dari 34 provinsi berjumlah 1.807 berusia minimal 15 tahun. Didapatkan proporsi pengetahuan salah
penggunaan masker adalah 8,9%, sikap wajib menggunakan masker tidak terjadi pada 0,8% responden,
perilaku selalu menggunakan masker 94,7%, dimana perilaku terendah pada responden laki-laki (92,3%), 15-
25 tahun (91,2%), dan pendidikan SMP (75,9%). Pengetahuan benar tentang menjaga jarak 92,8%, sikap
tidak setuju menjaga jarak 1,6%, dan perilaku selalu menjaga jarak 68,5%, dimana perilaku terendah pada
responden laki-laki (63,8%), 36-45 tahun (56,5%), pendidikan perguruan tinggi (66,1%). Pengetahuan benar
cuci tangan pakai sabun 94,9%, sikap benar 99,6%, dan perilaku responden yang selalu cuci tangan pakai
sabun 74,2%, dimana perilaku terendah pada responden laki-laki (69,0%), 15-25 tahun (70,3%),
berpendidikan SMP (51,7%).
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 75
Pengetahuan, sikap, dan perilaku 3M belum terlaksana secara menyeluruh dan konsisten saat Pandemi
COVID-19. Perlu dilakukan peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku 3M dengan lebih menggalakkan
kampanye baik tingkat nasional maupun daerah, menghadirkan agen perubahan, dan upaya promosi
kesehatan lainnya agar masyarakat meningkat kewaspadaannya untuk menjaga diri, keluarga, dan
lingkungannya.
Kata Kunci: COVID-19, masker, jaga jarak, CTPS
PENDAHULUAN
Pada tanggal 11 Maret 2020 World Health Organization (WHO) telah menyatakan bahwa
Corona virus disease -19 (COVID-19) sebagai pandemi karena telah menginfeksi 121.564 orang di
118 negara termasuk Indonesia. Penyebab penyakit ini adalah coronavirus yang merupakan
penyebab zoonosis yang pertama kali ditemukan di Wuhan China pada akhir tahun 2019 (1). Pada
tanggal 17 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia telah menyatakan tanggap darurat di
Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (2).
Peningkatan kasus COVID-19 baik di dunia maupun di Indonesia semakin hari semakin
mengkhawatirkan. Jumlah kasus COVID-19 di dunia per tanggal 7 Oktober 2020 adalah
36.080.088, dengan kasus kematian 1.055.236, dan kasus sembuh sebanyak 27.169.706. Sedangkan
untuk kasus COVID-19 di Indonesia, pada tanggal yang sama, jumlah kasus positif adalah 315.714,
kasus kematian 11.472, dan kasus sembuh 240.291 kasus (3).
COVID-19 bukan hanya memberikan dampak bagi kesehatan masyarakat saja, namun juga
memberikan dampak bagi perekonomian, pariwisata, pendidikan, dan aspek kehidupan masyarakat
lainnya. Tidak beraktivitasnya masyarakat dapat menyebabkan sektor ekonomi memburuk,
meningkatnya angka pengangguran, inflasi, meningkatnya angka putus sekolah, dan sebagainya.
Tenaga kesehatan, lanjut usia, anak – anak, dan ibu hamil juga merupakan kelompok rentan yang
akan terdampak dari pandemi COVID-19. Pelaku usaha kecil dan menengah juga termasuk
kelompok masyarakat yang mendapatkan pukulan yang paling terdampak dalam kehidupannya di
tengah Pandemi COVID-19 (4–7).
Pandemi COVID-19 dapat dikendalikan penyebarannya melalui berbagai upaya kesehatan
masyarakat, termasuk merubah perilaku masyarakat agar dapat mematuhi protokol kesehatan yang
sudah disosialisasikan oleh WHO maupun Pemerintah Indonesia. Perubahan atau adopsi perilaku
baru adalah suatu proses yang kompleks dan memerlukan waktu yang relatif lama. Secara teori,
perubahan perilaku atau seseorang dapat menerima atau mengadopsi perilaku baru dalam
kehidupannya melalui 3 tahap, yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan (8).
Penggunaan masker pada masyarakat dapat memberikan dampak yang menguntungkan
dalam mengurangi jumlah kasus dan kematian, dampak ini secara alami meningkat dengan
efektivitas penggunaan masker. Meskipun masih banyak ketidakpastian seputar keefektifan
sebenarnya dari masker wajah , terutama jika mempertimbangkan perbedaan jenis masker, tingkat
kepatuhan, dan pola perilaku manusia. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa masker dapat
memberikan perlindungan dan penahanan untuk virus pernapasan. Penggunaan masker wajah
dalam mengurangi penyebaran penyakit pandemi seperti COVID-19, yang merupakan salah satu
dari banyak strategi yang diterapkan secara bersamaan, termasuk social distancing, pembatasan
perjalanan, dan isolasi diri. Bahkan selama tindakan lock down di mana orang jarang meninggalkan
rumah mereka, banyak yang masih menghadapi pengaturan keluar rumah (misalnya melakukan
pekerjaan penting, perjalanan ke supermarket) meskipun lebih jarang. Penggunaan masker wajah
bisa menjadi komponen yang sangat penting mengurangi penularan setelah tindakan jarak sosial
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 76
dilonggarkan. Mempersiapkan pasokan masker wajah yang memadai untuk masa transisi seperti itu
dapat membantu mencegah puncak kedua (9).
Jarak sosial dengan menjaga jarak 1,5 m antar manusia, dapat mencegah penyebaran
sebagian besar penyakit infeksi saluran pernapasan. Jarak sosial adalah salah satu tindakan paling
efektif untuk mengurangi penyebaran virus, yang ditularkan melalui tetesan udara. Tetesan yang
dihasilkan oleh batuk, bersin atau berbicara memiliki jarak transmisi tertentu. Dengan menjaga
jarak, kita bisa mengurangi penyebaran virus. Memakai masker, sering mencuci tangan dan
mendisinfeksi dengan alkohol juga membantu mencegah penyebaran virus dari satu orang ke
orang lain. Dari pengalaman di China dengan pneumonia korona baru, bahwa jarak sosial adalah
tindakan yang paling efektif saat ini (10).
Sering mencuci tangan dengan sabun selama setidaknya 20 detik sangat disarankan sebagai
salah satu langkah preventif terhadap infeksi COVID-19. Namun, mengubah budaya mencuci
tangan di negara tertentu maupun secara global adalah tugas yang sulit, dengan mempertimbangkan
stabilitas perbedaan lintas budaya. Budaya mencuci tangan adalah prediktor yang sangat baik untuk
besarnya penyebaran COVID-19. Dari hasil analisis regresi terdapat korelasi yang kuat antara
budaya mencuci tangan dan besarnya wabah di berbagai negara. Secara spesifik, lokasi
masyarakatnya tidak memiliki kebiasaan mencuci tangan secara otomatis cenderung memiliki
eksposur yang jauh lebih tinggi terhadap COVID-19 (11). Dari delapan studi yang memenuhi
syarat melaporkan bahwa mencuci tangan menurunkan risiko infeksi pernapasan, mulai dari 6%
hingga 44% (nilai gabungan 24% (95% CI 6-40%). Mencuci tangan berhubungan dengan
rendahnya infeksi saluran pernapasan (12).
Dengan semakin meningkatnya penyebaran kasus COVID-19, dan telah terujinya efektivitas
menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun, dalam upaya mencegah
semakin meluasnya penularan, maka diperlukan penelitian yang dapat melihat proporsi
pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam melakukan tindakan 3 M. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana pengetahuan, sikap, dan perilaku 3 M ( memakai masker,
menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun) masyarakat di Indonesia pada masa pandemi
COVID-19.
METODE
Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional (potong lintang), dimana
variabel dependen dan independen diukur secara bersamaan dalam satu waktu tertentu, dan
menggunakan kerangka teori dari Lawrence Green tentang perilaku kesehatan (13). Populasi
adalah seluruh masyarakat Indonesia yang berdomisili di 34 provinsi. Sampel adalah masyarakat
Indonesia yang berdomisili di 34 provinsi, berusia minimal 15 tahun, dapat mengakses whatsapp,
dan bersedia berpartisipasi dalam survei daring yang tautannya disebarkan melalui jejaring
whatsapp (14).
Penghitungan jumlah sampel menggunakan rumus besar sampel estimasi proporsi seperti
di bawah ini :
dimana :
P=Estimasi proposi (50%)
d=simpangan mutlak (2,5%)
z=nilai z pada derajat kepercayaan 1-a/2 (5%3,84)
N= 1.537 ditambah 10% = 1.700. Sehingga jumlah sampel minimal adalah 1.700 orang responden.
2
2
2/1 )1(
d
PPzn
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 77
Sebelum dilakukan ujicoba kuesioner dan pengumpulan data, dilakukan kaji etik terlebih
dahulu dengan mengirimkan protokol penelitian kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan, Badan
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Selanjutnya mendapatkan Persetujuan Etik (Ethical
Approval) dengan Nomor LB.02.01/2/KE.320/2020 pada tanggal 23 April 2020 (15).
Pengumpulan data secara daring dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang dibuat
dengan menggunakan Google Forms dan tautannya (link) disebarkan melalui jejaring whatsapp.
Responden melakukan pengisian sendiri selama 6 – 10 menit, kemudian dikirimkan. Setelah data
terkumpul, kemudian dilakukan proses manajemen dan analisis data. Hanya dalam waktu 2 (dua)
hari sejak disebarkan, yaitu pada tanggal 30 April – 1 Mei 2020, sudah mendapatkan jumlah
sampel minimal yang dibutuhkan.
Kemudian dilakukan cleaning dan editing untuk menghindari nomor telepon yang sama, data
isian yang tidak lengkap, dan sebagainya. Data yang dikumpulkan dipastikan tidak mengandung
informasi sensitif responden, melainkan hanya menggunakan ID responden, provinsi, jenis
kelamin, umur, pendidikan, dan pekerjaan (14).
HASIL PENELITIAN
Karakteristik Responden
Gambaran sebaran responden dan karakteristiknya disajikan pada tabel 1 dan tabel 2. Setelah
dilakukan proses cleaning dan editing, berhasil didapatkan 1.807 responden yang berasal dari 34
provinsi.
Tabel 1. Distribusi Responden Menurut Provinsi dan Regional (N = 1.807) No Regional/Provinsi Jumlah Responden Persentase (%)
Regional Sumatera 443 24,5
1 Aceh 24 1,3
2 Sumatera Utara 34 1,9 3 Sumatera Barat 12 0,7
4 Riau 85 4,7
5 Kepulauan Riau 17 0,9
6 Jambi 23 1,3 7 Bengkulu 32 1,8
8 Sumatera Selatan 91 5,0
9 Bangka Belitung 10 0,6
10 Lampung 115 6,4
Regional Jawa – Bali 980 54,2
11 Banten 71 3,9
12 Jawa Barat 398 22,0
13 DKI Jakarta 187 10,3 14 Jawa Tengah 196 10,8
15 DI Yogyakarta 60 3,3
16 Jawa Timur 61 3,4
17 Bali 7 0,4
Regional Indonesia Bagian Timur 384 21,3
18 Nusa Tenggara Barat 8 0,4
19 Nusa Tenggara Timur 48 2,7
20 Kalimantan Utara 5 0,3 21 Kalimantan Barat 38 2,1
22 Kalimantan Tengah 5 0,3
23 Kalimantan Selatan 28 1,5
24 Kalimantan Timur 20 1,1 25 Gorontalo 14 0,8
26 Sulawesi Utara 23 1,3
27 Sulawesi Barat 16 0,9
28 Sulawesi Tengah 35 1,9 29 Sulawesi Selatan 59 3,3
30 Sulawesi Tenggara 51 2,8
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 78
31 Maluku Utara 3 0,2
32 Maluku 9 0,5
33 Papua Barat 4 0,2 34 Papua 18 1,0
Total 1.807 100
Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa sebaran responden pada 3 (tiga) provinsi dengan partisipasi
responden tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat (22,0%), Jawa Tengah (10,8%), dan DKI Jakarta
(10,3%) , sedangkan 3 (tiga) provinsi dengan partisipasi terendah adalah Papua Barat (0,2%),
Maluku Utara (0,2%), dan Kalimantan Utara (0,3%). Namun jika dibagi ke dalam regional, maka
partisipasi masyarakat di Regional Jawa – Bali persentasenya hampir sama dengan persentase
kumulatif Regional Sumatera dan Regional Indonesia Bagian Timur, yaitu 54,2% berbanding
24,5% dan 21,3%.
Tabel 2
Karakteristik Responden (N = 1.807)
Karakteristik n %
Jenis Kelamin
Laki – laki 583 32,3
Perempuan 1.224 67,7
Kelompok umur
15 15 – 25 tahun 468 25,9
26 – 35 tahun 599 33,1
36 – 45 tahun 395 21,9 46 – 55 tahun 249 13,8
56 – 65 tahun 71 3,9
>65 tahun 25 1,4
Pendidikan
Tidak sekolah 1 0,1
SD 8 0,4
SMP 29 1,6
SMA 345 19,1 Diploma/PT 1.424 78,8
Pekerjaan
Tidak bekerja 181 10,1
PNS/TNI/Polri 585 32,4 Karyawan Swasta/Buruh/Nelayan/Petani 523 28,9
Ibu Rumah Tangga 177 9,8
Pelajar/Mahasiswa 313 17,3
Lainnya 28 1,5
Berdasarkan tabel 2 di atas diketahui bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin
perempuan (67,7%), kelompok umur 26 – 35 tahun (33,1%), berpendidikan diploma atau pun
perguruan tinggi (78,8%), dan pekerjaan sebagai PNS/ASN/TNI/Polri (32,4%). Pada penelitian ini
didapatkan juga responden dengan kelompok usia 56 – 65 tahun (3,9%) dan usia lebih dari 65
tahun (1,4%), sedangkan mayoritas responden berada pada kisaran umur produktif. Responden
yang tidak sekolah hanya ada 1 orang saja (0,1%).
Pengetahuan
Pada tabel 3 di bawah ini disajikan pengetahuan responden tentang menggunakan masker,
menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun dapat mencegah penyebaran COVID-19 serta
melindungi diri dan keluarga dari bahaya COVID-19.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 79
Tabel 3. Distribusi Pengetahuan Responden tentang 3M di Masa Pandemi COVID-19 di
Indonesia (N = 1.807) Variabel Pengetahuan Pengetahuan Benar Pengetahuan Salah
n % n %
Memakai masker 1.647 91,1 160 8,9 Menjaga jarak 1.677 92,8 130 7,2
Mencuci tangan dengan sabun 1.715 94,9 92 5,1
Pengetahuan benar adalah bahwa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan
dapat melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya dari bahaya penyebaran kasus COVID-
19. Pada tabel 3 diketahui bahwa pengetahuan benar paling tinggi persentasenya pada mencuci
tangan dengan sabun (94,9%), kemudian menjaga jarak (92,8%), dan terakhir adalah memakai
masker (91,1%).
Masih terdapat 8,9% responden yang belum memahami bahwa memakai masker dapat
mencegah tertular COVID-19. Demikian juga untuk himbauan di rumah saja dan menjaga jarak
masih belum dipahami oleh 7,2% responden, dan mencuci tangan dengan sabun dapat menghindari
penularan COVID-19 juga masih belum diketahui oleh 5,1% responden.
Sikap
Proporsi sikap responden terkait dengan 3M adalah dikatakan setuju jika responden sepakat
bahwa setiap keluar rumah wajib menggunakan masker, setuju untuk lebih banyak melakukan
aktivitas di dalam rumah saja untuk menjaga jarak fisik dan sosial, dan sepakat dengan adanya
himbauan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin.
Tabel 4. Distribusi Sikap Responden tentang 3M di Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia
(N= 1.807) Variabel Sikap Sikap Setuju Sikap Tidak setuju
n % n %
Wajib memakai masker jika keluar rumah 1.792 99,2 15 0,8
Himbauan selalu di rumah saja 1.778 98,4 29 1,6
Himbauan selalu mencuci tangan dengan
sabun sesering mungkin
1.800 99,6 7 0,4
Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa sikap tidak setuju responden atas adanya himbauan 3M
hanya di bawah 2% untuk ketiga item cara pencegahan penularan COVID-19. Sebanyak 99,6%
responden setuju bahwa harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesering mungkin,
99,2% setuju untuk wajib memakai masker jika beraktivitas di luar rumah, dan sebanyak 98,4%
responden setuju atas adanya himbauan untuk selalu berada di dalam rumah saja untuk menjaga
jarak fisik agar tidak berada dalam kerumunan.
Perilaku
Distribusi perilaku responden dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini. Sama halnya dengan
item pengetahuan dan sikap, maka perilaku juga melihat ketiga item pencegahan penularan
COVID-19.
Tabel 5.Distribusi Perilaku Responden tentang 3M di Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia
(N=1.807) Variabel Perilaku Ya Perilaku Tidak
n % n %
Selalu memakai masker 1.711 94,7 96 5,3 Selalu beraktivitas di rumah 1.238 68,5 569 31,5
Selalu mencuci tangan dengan
sabun dan air mengalir selama 20
detik
1.341 74,2 466 25,8
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 80
Pada tabel 5 disajikan tentang perilaku responden terkait dengan memakai masker, menjaga
jarak/beraktivitas di rumah, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik.
Berbeda halnya dengan pengetahuan dan sikap, persentase perilaku 3M responden lebih rendah.
Perilaku terendah adalah selalu menjaga jarak atau beraktivitas di dalam rumah saja (68,5%),
selanjutnya adalah perilaku selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik
(74,2%). Selain itu juga masih ada 5,3% responden yang tidak selalu memakai masker setiap
beraktivitas di luar rumah.
Tabel 6. Persentase Pengetahuan Salah, Sikap Tidak Setuju, dan Perilaku Tidak Melakukan
3M di Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia Menurut Karakteristik Responden (N = 1.807)
Karakteristik Pengetahuan Salah (%) Sikap Tidak Setuju (%) Perilaku Tidak Melakukan (%)
Responden Masker Jaga
jarak
CTPS Masker Jaga
jarak
CTPS Masker Jaga
jarak
CTPS
Jenis Kelamin
Laki – laki 10,8 10,3 7,7 1,9 3,1 0,9 7,7 36,1 31,1
Perempuan 7,9 5,7 3,8 0,3 0,9 0,2 4,2 29,3 23,3
Kelompok umur
16 15 – 25 tahun 13,9 8,3 4,3 1,3 1,5 0,2 8,7 20,8 29,7
26 – 35 tahun 7,5 7,0 4,8 0,7 2,5 0,5 4,8 33,4 26,1 36 – 45 tahun 6,1 7,6 5,6 0,8 1,3 0,0 3,8 43,5 24,1
46 – 55 tahun 6,4 4,4 4,0 0,4 0,8 0,8 2,4 34,1 21,7
56 – 65 tahun 9,9 5,6 11,3 1,4 0,0 0,0 7,0 18,3 26,8
>65 tahun 12,0 16,0 12,0 0,0 0,0 4,0 0,0 8,0 12,0
Pendidikan
Tidak sekolah* 0,0 100 100 0,0 100 0,0 0,0 100 0,0
SD 25,0 12,5 12,5 0,0 0,0 37,5 12,5 25,0 37,5
SMP 27,6 20,7 10,3 0,0 3,4 48,2 24,1 20,7 48,2
SMA 11,3 8,4 5,5 1,7 2,0 30,2 9,0 22,4 30,2
Diploma/PT 7,8 6,5 4,8 0,7 1,4 24,3 4,0 33,9 24,3
Pekerjaan
Tidak bekerja 5,0 9,4 5,5 0,0 1,7 0,6 7,2 21,5 23,8 PNS/TNI/Polri 6,3 6,2 3,8 0,5 0,9 0,3 3,4 41,1 24,4
Swasta/Buruh/Nelayan/Petani 9,6 7,6 5,5 1,0 2,1 0,4 4,6 41,5 26,2
Ibu Rumah Tangga 7,3 5,6 6,2 0,6 2,8 0,0 4,0 17,0 23,2 Pelajar/Mahasiswa 15,0 8,0 5,4 1,9 1,6 0,3 10,2 11,8 31,6
Lainnya 14,3 7,1 10,7 0,0 0,0 3,6 0,0 21,5 10,7
Ket :* jumlah responden yang tidak sekolah hanya 1 orang saja
Pada tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa pengetahuan salah tentang manfaat masker dapat
mencegah COVID-19 tertinggi terjadi pada laki – laki (10,8%), berusia 15 – 25 tahun (13,9%),
berpendidikan SMP (27,6%), dan pelajar/mahasiswa (15,0%). Sedangkan untuk sikap yang tidak
setuju bahwa mencuci tangan dengan sabun dapat mencegah penularan COVID-19 lebih besar
terjadi di responden laki – laki (0,9%), berusia lebih dari 65 tahun (4,0%), berpendidikan SMP
(48,2%), dan pekerjaan lainnya (3,6%).
Perilaku responden yang tidak selalu menggunakan masker saat keluar rumah banyak terjadi
pada laki – laki (7,7%), berusia 15 – 25 tahun (8,7%), berpendidikan SMP (24,1%), dan pekerjaan
sebagai pelajar/mahasiswa (10,2%). Sedangkan dari 31,5% responden yang tidak menjaga jarak,
persentase tertinggi terjadi pada responden laki – laki (36,1%), berusia 36 – 45 tahun (43,5%),
berpendidikan Diploma/Perguruan Tinggi (33,9%), pekerjaan Pegawai
Swasta/Buruh/Nelayan/Petani (41,5%). Perilaku tidak selalu (hanya kadang – kadang, jarang, atau
bahkan tidak pernah) cuci tangan pakai sabun selama minimal 20 detik banyak terjadi pada
responden laki – laki (31,1%), berusia 15 – 25 tahun (29,7%), berpendidikan SMP (48,2%),
pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa (31,6%).
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 81
PEMBAHASAN Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini merupakan survei daring dengan menyebar kuesioner melalui media sosial.
Cara ini paling mudah, murah, dan cepat, apalagi di saat pandemi seperti ini, dimana kontak fisik
harus sangat diminimalisir. Survei daring dengan menggunakan Google Forms merupakan salah
satu cara yang cepat, real time, aman, mudah digunakan, dan data yang masuk juga bisa langsung
dianalisis (16). Namun kelemahan dari survei daring ini adalah responden tidak bisa diprobing
maupun diklarifikasi.
Pada saat penelitian dilakukan, kampanye jaga jarak 1 – 2 meter belum dilakukan oleh
pemerintah, melainkan baru himbauan untuk tetap berada di dalam rumah saja, beraktivitas
bekerja/sekolah/ibadah dan sebagainya di dalam rumah, sehingga perilaku untuk selalu beraktivitas
di dalam rumah diasumsikan sebagai perilaku menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
Karakteristik Responden
Penyebaran kuesioner melalui jejaring whatsapp, sehingga tidak bisa dikontrol distribusi
sebaran sampelnya, hal ini menyebabkan distribusi sampel dari ke-34 provinsi tidak merata dan
tidak proporsional dalam hal karakteristik wilayah dan individu. Secara karakteristik individu,
sebaran sampel lebih dominan kepada responden dengan pendidikan tinggi (78,8%), hal ini
mungkin terjadi karena sebaran di whatsapp group yang memang terkumpul pada karaktertisk
tertentu. Untuk jenis kelamin, juga lebih banyak responden perempuan (67,7%) yang berpartisipasi
dibandingkan dengan responden laki – laki (23,3%), sedangkan untuk karakteristik umur dan
pekerjaan cenderung tidak ada karakteristik tertentu yang mendominasi.
Hal ini serupa dengan hasil survei daring Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 yang
mendapatkan responden terbesar berdomisili di Pulau Jawa (58,48%). Jumlah responden
perempuan lebih tinggi daripada responden laki – laki dan responden dengan persentase tertinggi
pendidikannya adalah mereka yang perguruan tinggi (71,0%) (17) .
Pengetahuan
Menurut teori Green, pengetahuan adalah domain penting untuk terbentuknya tindakan dan
penerimaan perilaku baru yang bersifat long lasting. Sebaliknya, apabila perilaku itu tidak disadari
oleh pengetahuan dan kesadaran akan tidak berlangsung lama, karena orang yang sudah tahu
(awareness) terhadap suatu hal belum tentu dia akan berperilaku yang benar sebelum yang
bersangkutan melakukan beberapa tahap sampai pada akhirnya dia mengadopsi hal tersebut dengan
tepat (13).
Hasil penelitian Brienen, et al. pada tahun 2010 menunjukkan bahwa penggunaan masker
wajah pada tingkat populasi dapat menunda pandemi influenza, menurunkan tingkat serangan
infeksi, dan dapat mengurangi penularan untuk menahan pandemi. Efek penggunaan masker
diilustrasikan oleh tiga contoh berikut : 1)Penggunaan masker tidak hanya melindungi individu
yang sehat tetapi juga mengurangi penularan dari pembawa yang bergejala dan tanpa gejala,
sehingga mengurangi jumlah dan efektivitas sumber penularan dalam populasi; 2)Mengenakan
masker dapat meningkatkan kesadaran akan risiko infeksi dan pentingnya perilaku pencegahan
tambahan seperti lebih sering mencuci tangan atau menghindari kontak fisik dan menghindari
tempat umum yang ramai. Masker wajah juga dapat mengurangi penularan kontak dengan
mencegah pemakainya menyentuh mulut atau hidung dengan tangan atau benda lain yang
berpotensi terkontaminasi virus; 3) Penggunaan masker hampir menjadi satu-satunya cara untuk
mencegah penularan aerosol, yang dapat menyebabkan kasus influenza yang paling parah. Namun,
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 82
di sisi lain, penggunaan masker wajah dapat menimbulkan rasa aman yang salah dengan
mengurangi tindakan kebersihan diri. Penggunaan masker wajah di seluruh populasi bisa menjadi
strategi yang berharga untuk menunda atau menahan pandemi influenza, atau setidaknya
menurunkan tingkat serangan infeksi (18). Hal ini selaras dengan penelitian ini, yaitu pengetahuan
responden tentang memakai masker dan cuci tangan dengan sabun relatif sudah baik (di atas 95%),
namun pengetahuan penggunaan masker dan cuci tangan pakai sabun dapat mencegah penyebaran
infeksi COVID-19 paling rendah berada pada kelompok usia lanjut usia, dan juga responden yang
berpendidikan rendah (SD – SMP).
Himbauan yang dikeluarkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini
adalah dengan melakukan social distancing atau pembatasan sosial, dimana dianjurkan untuk
mengurangi aktivitas di luar rumah sehingga diharapkan bekerja, belajar, dan beribadah dilakukan
dari rumah. Diharapkan dengan melakukan hal ini maka penyebaran virus tidak akan meluas.
Pengetahuan responden mengenai anjuran bahwa dengan di rumah saja dapat mencegah penularan
COVID-19 sudah sangat baik dimana terdapat 92,8% responden menjawab benar.
Di Indonesia, pemerintah daerah juga telah melakukan beberapa kebijakan social distancing
seperti meliburkan sekolah dan menutup tempat-tempat wisata, mengimbau perusahaan-perusahaan
untuk menerapkan bekerja dari rumah (work from home), meniadakan kegiatan-kegiatan massal di
tempat ibadah, hingga membatasi waktu operasional transportasi umum. Meski membatasi
pergerakan orang-orang tidak langsung menghentikan pandemi, tapi cara ini diyakini dapat
mengurangi angka penularan COVID-19, mencegah infeksi virus pada mereka yang masih sehat
sehingga memberikan waktu bagi para petugas medis untuk menyembuhkan pasien positif.
Secara umum diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang mencuci tangan
pakai sabun (ctps) sudah baik. persentase pengetahuan ctps yang benar secara persentase lebih
tinggi pada perempuan daripada laki-laki (96 % vs 92%). Ditinjau dari rutinitas melakukan
aktivitas ctps responden perempuan juga lebih tinggi proporsinya daripada laki-laki. Namun, bila
dilihat dari latar belakang pendidikan, responden yang berpendidikan SMP lebih sedikit melakukan
ctps dengan air mengalir selama minimal 20 detik.
Sikap
Cuci tangan pakai sabun adalah salah satu tindakan sanitasi sehingga tidak mengherankan
bahwa proporsi penduduk yang menggunakan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air on
premises adalah salah satu dari indikator SDG yaitu indikator 6.2.1b (19). Namun pada
kenyataannya praktek ctps tidak serta merta dilakukan oleh semua orang. Penelitian yang dilakukan
oleh Wolf, et al 2019 menginformasikan bahwa satu dari empat orang di dunia tidak memiliki
akses fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air on premises di tahun 2015. Pada periode yang
sama, praktek ctps hanya sekitar 26% pada kegiatan yang berpotensi kontak dengan fecal. Di
wilayah yang akses fasilitas ctps bagus, praktek ctps dilakukan oleh 51% penduduk dan di wilayah
dengan akses yang terbatas, praktek ctps hanya dilakukan oleh 22% penduduk setelah kegiatan
yang berpotensi kontak dengan fecal (20).
Ada sejumlah faktor psikologis yang secara halus membuat seseorang enggan mencuci
tangan, yaitu cara berfikir hingga tingkat optimisme delusi/bias optimisme, kebutuhan untuk
merasa ‗normal‘ dan perasaan jijik yang dimiliki. Adanya optimisme delusi atau bias optimisme
menyebabkan seseorang merasa percaya diri dengan menganggap hal-hal buruk akan lebih kecil
kemungkinannya untuk dialami. Sebuah studi menunjukkan bahwa kaum perempuan jauh lebih
rajin mencuci tangan dibanding kaum lelaki. Tren ini berlanjut hingga dari suatu jejak pendapat
diketahui sebanyak 65% perempuan mencuci tangan rutin sedangkan laki-laki hanya 52%. Selain
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 83
itu perilaku kepatuhan mencuci tangan lebih dominan dilakukan pada orang yang memiliki sifat
telaten dan memiliki rasa jijik, sehingga efektif untuk membuat orang melakukan ctps (21).
Saat pandemi ini sangat dianjurkan untuk mengintensifkan kegiatan ctps. Virus Sars-CoV2
sebagai penyebab COVID-19 menyebar melalui droplet dan transmisi kontak, yaitu adanya kontak
antara tangan dengan penderita atau objek maupun permukaan yang terkontaminasi, selanjutnya
masuk ke mulut ataupun mata. Waktu yang krusial untuk melakukan cuci tangan antara lain setelah
batuk/bersin, merawat pasien, sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum makan,
setelah dari toilet, ketika tangan terlihat kotor dan setelah membersihkan kotoran hewan. Durasi
mencuci tangan yang dianjurkan oleh WHO adalah 20-30 detik bila menggunakan larutan berbasis
alcohol, dan bila menggunakan air dan sabun minimal 40-60 detik (22).
Selaras dengan penelitian di atas, maka pada penelitian ini hampir semua (99,6%) responden
menyatakan sikap setuju mengenai adanya himbauan pemerintah untuk selalu mencuci tangan
pakai sabun dan air mengalir sesering mungkin. Hanya 0,4% responden yang menyatakan sikap
tidak setuju untuk ctps. Mereka yang berusia > 65 tahun, berpendidikan SMP, dan berpekerjaan
lainnya merupakan kelompok responden dengan persentase tertinggi untuk bersikap tidak setuju
bahwa ctps dapat mencegah penularan COVID-19.
Perilaku
Pemakaian masker secara universal oleh publik adalah kebijakan penting untuk mengurangi
penularan COVID-19, terutama ketika negara-negara selesai dari lock down. Kita perlu mengurangi
bicara, dan mereka yang memiliki gejala batuk dan bersin harus mengisolasi diri. Kondisi normal
baru ini perlu dilanjutkan sampai ada perawatan farmakologis yang aman dan efektif serta vaksin
melawan COVID-19. Masker memberikan perlindungan yang lebih baik bila dikombinasikan
dengan tindakan perlindungan lainnya termasuk sering mencuci tangan dengan sabun dan air
mengalir, tidak menyentuh wajah, etika pernapasan, solidaritas sosial, dan jarak fisik (23).
Perilaku terendah selalu menjaga jarak/melaksanakan himbauan di rumah saja terdapat pada
kelompok responden laki-laki (63,8%), 36-45 tahun (56,5%), pendidikan perguruan tinggi (66,1%).
Hal ini dapat disebabkan karena kelompok-kelompok ini merupakan kelompok usia produktif. Di
masa pandemi ini banyak terjadi ketidakpastian karena hal yang baru. Ketidakpastian kapan
penyebaran virus ini akan berakhr, keharusan mengisolasi diri, menggunakan masker,
meningkatkan imunitas diri, dan lain-lain. Kondisi ini mempengaruhi tingkat imunitas dan
kejiwaan masyarakat. BPS menyatakan bahwa 69,43% respondennya menyatakan sangat khawatir
atau khawatir terkait kesehatan dirinya saat harus beraktivitas di luar rumah (17).
Pemberlakuan social atau physical distancing juga diikuti dengan kebijakan bekerja dan
bersekolah dari rumah. Menurut BPS (2020) persentase responden yang selalu WFH (work from
home) sejak ditetapkan adalah mereka yang berpendidikan perguruan tinggi. Hal ini berbanding
terbalik dengan hasil penelitian ini dimana persentase selalu di rumah saja pada kelompok
pendidikan terakhir dengan persentase paling rendah yaitu perguruan tinggi (66,1%) (17). Hal ini
mungkin terjadi karena jenjang pekerjaan pendidikan ini kemungkinan sudah berada pada level
manajemen yang perlu ada di kantor atau jenis pekerjaan yang mengharuskan berada di lapangan
atau kantor.
Aktivitas mencuci tangan merupakan salah satu upaya pencegahan penyakit karena dengan
membersihkan tangan menggunakan air dan sabun maka dapat memutuskan mata rantai kuman
yang sering melekat di tangan dan berpindah ketika adanya kontak langsung maupun tidak
langsung. Kuman tersebut berupa bakteri, virus dan parasit yang bersumber dari kotoran
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 84
hewan/manusia, cairan tubuh, ataupun makanan dan minuman yang sudah tercemar sebelumnya
ketika dikonsumsi.
Beberapa studi membuktikan manfaat dari ctps dalam mencegah penyakit infeksi, seperti
diare, infeksi saluran pernafasan, pneumonia, dan lain-lain. Penelitian yang dilakukan oleh Luby
tahun 2011 menggunakan analisis multivariat diperoleh adanya asosiasi antara praktek cuci tangan
ibu dengan rendahnya kasus diare anak dan infeksi pernafasan. Selain itu penelitian yang lain
menunjukkan bahwa cuci tangan dengan sabun non antiseptic jauh lebih efektif menghilangkan
kuman di tangan daripada cuci tangan dengan air saja (24). Terkait dengan pandemi COVID-19 ini,
studi yang dilakukan di Inggris pada tahun 2007 menyatakan bahwa mencuci tangan dengan sabun
secara teratur dengan disertai penggunaan masker, sarung tangan dan pelindung, bisa jadi lebih
efektif dalam mencegah penyebaran virus ISPA seperti flu dan SARS (25).
Pencegahan penyebaran COVID-19 melalui praktek perilaku aman dan sehat merupakan hal
penting. Penyediaan air yang aman, sanitasi dan kondisi yang higienis merupakah hal-hal yang
mendasar untuk melindungi selama adanya Kejadian Luar Biasa (KLB), termasuk pandemi
COVID-19. Kebersihan tangan yang tepat merupakan pertahanan pertama dalam melawan
transmisi penyakit ini dan telah dibuktikan sebagai cara yang paling efektif, murah dan mudah
dalam menjaga kesehatan dari ancaman infeksi. Oleh sebab itu, penting sekali menjamin
ketersediaan fasilitas cuci tangan yaitu air bersih dan sabun, di tempat-tempat strategis misalnya
sekolah, area publik, pasar, tempat kerja, dan fasilitas kesehatan.
Gerakan sosialisasi 3M di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) gencar dilakukan oleh
Pemerintah baik tingkat Pusat maupun Daerah. Gerakan 3M tersebut meliputi memakai masker,
mencuci tangan dan menjaga jarak sebagai upaya pencegahan memutus mata rantai penularan
COVID-19. Kampanye 3M digalakkan oleh Pemerintah melalui berbagai media baik cetak maupun
elektronik (26).
Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Nasional menyatakan bahwa semakin
banyak menjaga jarak, memakai masker dengan benar, dan sering mencuci tangan dengan sabun,
maka pandemi ini akan semakin cepat berlalu. Dalam menghadapi AKB, masyarakat harus
memahami bahwa dalam melakukan segala aktivitas tidak sama seperti kehidupan normal saat
sebelum pandemi. Masyarakat dihimbau hanya keluar rumah jika memang benar – benar perlu,
terutama bagi yang berisiko tinggi, termasuk para lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit
jantung, hipertensi, diabetes, dan paru (27). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan
lansia tentang 3 M merupakan yang paling rendah persentasenya diantara kelompok umur lainnya,
tetapi tidak demikian untuk sikap dan perilakunya.
Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2020 mengeluarkan revisi SKB 4 Menteri (Mendiknas,
Menkes, Menag, dan Mendagri) mengenai Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi
COVID-19, yang menyatakan bahwa untuk mengantisipasi konsekuensi negatif dan isu
pembelajaran jarak jauh, pemerintah mengimplementasikan dua kebijakan baru, yaitu perluasan
pembelajaran tatap muka untuk zona kuning dan kurikulum darurat dalam kondisi khusus.
Pelaksanaan pembelajaran tatap muka diperbolehkan untuk semua jenjang yang berada pada zona
hijau dan zona kuning (28). Dengan adanya kebijakan ini, harus disikapi dengan hati – hati, karena
menurut hasil temuan penelitian ini menyatakan bahwa perilaku tidak menggunakan masker dan
tidak cuci tangan pakai sabun paling banyak terjadi pada responden usia sekolah dan pekerjaan
pelajar/mahasiswa. Sosialisasi baik di tingkat sekolah/kampus maupun lingkungan sekitar harus
lebih gencar lagi dilakukan agar para pelajar dan mahasiswa lebih disiplin melakukan upaya 3M.
Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah, TNI, Polri, dan Satpol PP guna menekan
penyebaran COVID-19 membutuhkan modal cukup besar, demikian juga halnya dengan pengadaan
vaksin yang tengah diupayakan Pemerintah. Vaksin yang paling murah adalah Iman, Aman, dan
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 85
Imun; yaitu dengan percaya bahwa pandemi ini terjadi atas izin Tuhan Yang Maha Esa, Aman
dengan menerapkan perilaku 3M, dan Imun dengan mengkonsumi vitamin, berolahraga, konsumsi
makanan sehat, dan istirahat yang cukup (29).
KESIMPULAN DAN SARAN
Kampanye 3M saat ini semakin digencarkan oleh Pemerintah, karena menjadi cara utama
dan paling mudah dan murah dalam pencegahan penyebaran COVID-19 secara lebih meluas,
selama vaksin dan obat yang tepat belum ditemukan. Namun dari hasil penelitian ini diketahui
bahwa pengetahuan dan sikap masyarakat Indonesia terkait 3M (memakai masker, menjaga jarak,
dan mencuci tangan dengan sabun) relatif sudah cukup baik, namun tidak diiringi dengan
perilakunya. Masih ada sekitar 1 dari 3 – 4 masyarakat Indonesia yang belum berperilaku selalu
menjaga jarak/beraktivitas di dalam rumah saja dan mencuci tangan pakai sabun.
Saran dari penelitian ini adalah perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan
pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat Indonesia dengan mengupayakan kegiatan promotif
dan preventif yang melibatkan lintas program dan lintas sektor dengan menggunakan budaya lokal
sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat, menghadirkan agen perubahan perlaku, dan
promosi kesehatan lainnya agar masyarakat Indonesia dapat meningkat kewaspadaannya untuk
menjaga diri, keluarga, dan lingkungannya.
DAFTAR PUSTAKA
1. CNN. WHO Umumkan Virus Corona Sebagai Pandemi [Internet]. Jakarta; 2020 [cited 2020
Mar 15]. Available from: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200312000124-
134-482676/who-umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi
2. BNPB. Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat COVID-19 di
Indonesia. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Jakarta; 2020.
3. Worldometer. COVID-19 Coronavirus Pandemic [Internet]. 2020 [cited 2020 Oct 7].
Available from: https://www.worldometers.info/coronavirus
4. Hanoatubum S. Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. EduPsyCouns.
2020;2(1).
5. Purwanto A, Pramono R, Asbari M, Santoso PB, Mayesti L. Studi Eksploratif Dampak
Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar.
EduPsyCouns. 2020;2(1).
6. Pradana AA, Casman C, Nur‘aini N. Pengaruh Kebijakan Social Distancing pada Wabah
COVID-19 terhadap Kelompok Rentan di Indonesia. J Kebijak Kesehat Indones JKKI
[Internet]. 2020;9(2):61–7. Available from: https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/55575
7. Thaha AF. Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. J Brand. 2020;2(1):147–53.
8. Notoatmodjo S. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta: Rineka Cipta; 2007.
9. Worby CJ, Chang HH. Face mask use in the general population and optimal resource
allocation during the COVID-19 pandemic. Nat Commun. 2020;11(1).
10. Qian M, Jiang J. COVID-19 and social distancing. J Public Heal. 2020;(Mikulska 2019).
11. Pogrebna G, Kharlamov AA. The Impact of Cross-Cultural Differences in Handwashing
Patterns on the COVID-19 Outbreak Magnitude. Res Gate [Internet]. 2020;(March):10.
Available from: https://www.researchgate.net/publication/340050986%0AThe
12. Rabie T, Curtis V. Handwashing and risk of respiratory infections: A quantitative
systematic review. Trop Med Int Heal. 2006;11(3):258–67.
13. Green L, Kreuter MW. Health Program Planning : An Educational and Ecological
Approach. 4th ed. New York: McGraw-Hill; 2005.
14. Cahyorini, Dkk. Laporan Penelitian Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Hidup Sehat
Masyarakat Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 di Indonesia. Jakarta: Badan
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 86
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kemenkes RI; 2020.
15. KEPK-BPPK. Persetujuan Etik untuk Penelitian PSP Hidup Sehat Masyarakat dalam
Menghadapi Pandemi COVID-19 di Indonesia, No. LB.02.01/2/KE.320/2020 tanggal 23
April 2020. 2020.
16. Sudaryo Y, Sofiati NA, Medidjati A, Hadiana A. Metode Penelitian Survei Online dengan
Google Forms. Risanto E, editor. Yogyakarta: ANDI; 2019.
17. Badan Pusat Statistik. Hasil Survei Sosial Demografi Dampak COVID-19 Tahun 2020.
Jakarta: BPS RI; 2020.
18. Brienen NCJ, Timen A, Wallinga J, Steenbergen JE Van, Teunis PFM. The Effect of Mask
Use on the Spread of Influenza During a Pandemic. 2010;30(8):1210–8.
19. Kementerian PPN/Bappenas. Ringkasan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia. 2017.
20. Wolf J, Johnston R, Freeman MC, Ram PK, Slaymaker T, Laurenz E, et al. Handwashing
with soap after potential faecal contact: Global, regional and country estimates. Int J
Epidemiol. 2019;48(4):1204–18.
21. Burton M, Cobb E, Donachie P, Judah G, Curtis V. The Effect of Handwashing with Water
or Soap on Bacterial Contamination of Hands. Int J Environ Res Public Health. 2011;8:97–
104.
22. WHO. Who Save Lives : Clean Your Hands in the Context of Covid-19. 2020;(May):19–20.
Available from: https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-
hands/en/%0Ahttps://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-
hands/WHO_HH-Community-Campaign_finalv3.pdf?ua=1
23. Liu C, Diab R, Naveed H, Leung V. Universal public mask wear during COVID-19
pandemic: Rationale, design and acceptability. Respirology. 2020;25(8):895–7.
24. Luby SP, Halder AK, Huda TMN, Unicomb L, Johnston RB. Using child health outcomes
to identify effective measures of handwashing. Am J Trop Med Hyg. 2011;85(5):882–92.
25. Suryani SI, Sodik MA. Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun. Jakarta: Pusdatin Kemenkes RI;
2018.
26. Suaramerdeka.com. Pemerintah Gencar Kampanye 3M, Apa Isinya? [Internet]. 2020 [cited
2020 Sep 1]. Available from: https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/237900-
pemerintah-gencar-kampanye-3m-apa-isinya
27. BNPB. Ketahui: Adaptasi Kebiasaan Baru [Internet]. 2020 [cited 2020 Jul 1]. Available
from: https://covid19.go.id/edukasi/apa-yang-harus-kamu-ketahui-tentang-covid-
19/adaptasi-kebiasaan-baru
28. BNPB, Kemendiknas, Kemenkes, Kemenag, Kemendagri. Penyesuaian Kebijakan
Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 [Internet]. Jakarta: Satgas COVID-19 Nasional;
2020. Available from: https://covid19.go.id/
29. BNPB. Perubahan Perilaku Jadi Kunci Pencegahan COVID-19 [Internet]. 2020 [cited 2020
Oct 7]. Available from: https://covid19.go.id/p/berita/perubahan-perilaku-jadi-kunci-
pencegahan-covid-19
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 87
EVALUASI PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN K3 PRESSURE VESSEL OLEH
AHLI K3 PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN BERDASARKAN
PERMENAKER NO. 37 TAHUN 2016 DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELIT UNG PADA TAHUN 2018 DAN 2019
Maududi Farabi, SKM,
1 Mila Tejamaya, S.Si., MOHS., Ph.D.,
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
Corresponding email: [email protected]
EVALUATION OF PRESSURE VESSEL INSPECTION BY OHS EXPERT BASED ON
THE REGULATION OF THE MINISTER OF R.I. MANPOWER NO. 37 OF 2016 IN
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE YEAR OF 2018 AND 2019
ABSTRACT
The usage of pressure vessels has recently increase in various business sectors. Even though the use of
pressure about many benefits, also creates multiple Occupational Safety and Health (OHS) potential
hazards, including: high levels of pressure which have the potential to cause leakage, explosion, fire and
work accidents. All types of pressure vessel usage must undergo OHS inspection before hand in accordance
with the applicable provisions and standards. If the implementation of pressure vessel OHS inspections were
to be of low quality, this may increase the risk of blasting and other work accidents. The purpose of writing
this publication is to analyze OHS requirements from the pressure vessel OHS inspection reports by OHS
experts (AK3) pressure vessel specialist (PUBT) that has not yet met to the Regulation of the Minister of
Manpower (Permenaker) R.I. No. 37 of 2016. This research uses a qualitative observational analytic study
report approach. The method of sampling of this study is performed by the total population, that is all the
results of the inspection and testing of pressure vessels by the PUBT Specialist AK3 in the Bangka Belitung
Islands Province Employment Agency, amounting to 40 reports in 2018 and 50 reports in 2019. The results
of the study indicates that there were some test examinations and pressure vessel OHS inspections report
made by AK3 PUBT specialists which have not fulfilled the requirements, including administrative
inspection, incomplete technical drawings, calibration of test equipment, implementation of non-destructive
testing, compaction testing, implementation of safety testing (safety devices), as well as incomplete
calculations for the strength of construction. Coaching, monitoring, and a more stringtent evaluation process
and media are needed to ensure that pressure vessel OHS inspection by AK3 PUBT has met to the
Regulation and standard.
Keywords: pressure vessel, OHS inspection, the Regulation of R.I. MinisterManpower No. 37 of 2016
ABSTRAK
Penggunaan bejana tekanan atau pressure vessel semakin meningkat di berbagai sektor usaha. Di samping
manfaat yang besar, pemakaian Bejana Tekanan mengandung potensi bahaya Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3), diantaranya: tekanan yang tinggi yang berpotensi menyebabkan kejadian kebocoran, peledakan,
kebakaran dan kecelakaan kerja. Setiap penggunaan pressure vessel harus dilakukan pemeriksaan dan
pengujian (riksa uji) K3 sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Rendahnya kualitas pelaksanaan
Riksa Uji K3 pressure vessel di tempat kerja dapat mempertinggi risiko peledakan dan kecelakaan kerja
lainnya. Tujuan dari penulisan publikasi ini untuk menganalisa syarat-syarat K3 apa saja dari laporan riksa
uji K3 pressure vessel oleh Ahli K3 (AK3) spesialis pesawat uap bejana tekanan (PUBT) yang belum
memenuhi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) R.I. No. 37 Tahun 2016. Jenis penelitian ini
adalah deskriptif analitik kualitatif dengan membandingkan pemeriksaan dan pengujian K3 pressure vessel
yang dilakukan oleh AK3 spesialis PUBT di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 dan tahun
2019 dengan Permenaker R.I. No. 37 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder seluruh hasil
pemeriksaan dan pengujian AK3 spesialis PUBT tahun 2018 dan 2019 sebanyak 90 laporan. Hasil penelitian
didapatkan masih ada kegiatan riksa uji dan pembuatan laporan riksa uji K3 pressure vessel oleh AK3
spesialis PUBT yang belum memenuhi persyaratan antara lain tidak dilakukannya pemeriksaan administrasi,
ketidaklengkapan gambar teknis, pelaksanaan kalibrasi peralatan uji, pelaksanaan pengujian tidak merusak
(Non Destructive Test), pelaksanaan pengujian pemadatan, pelaksanaan pengujian alat-alat pengaman (safety
devices), serta ketidaklengkapan perhitungan ulang kekuatan konstruksi. Pembinaan, pengawasan, media
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 88
dan proses evaluasi yang lebih ketat sangat dibutuhkan untuk menjamin pelaksanaan riksa uji K3
pressure vessel telah memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan dan standar yang berlaku.
Kata Kunci: Bejana tekanan, riksa uji k3, permenaker 37 tahun 2016
PENDAHULUAN
Bejana tekanan adalah bejana selain pesawat uap yang di dalamnya terdapat tekanan dan
dipakai untuk menampung gas, udara, campuran gas, atau campuran udara baik dikempa menjadi
cair dalam keadaan larut maupun beku.1 Contoh bejana tekanan antara lain: air receiver tank,
bejana transport, bejana penyimpanan bahan bakar gas untuk kendaraan, botol baja oksigen, botol
baja acetylene, botol hydrogen, botol LPG, dan sebagainya. Penggunaan bejana tekanan atau
pressure vessel semakin meningkat di berbagai sektor usaha. Di samping manfaat yang besar,
pemakaian bejana tekanan mengandung potensi bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),
diantaranya: tekanan yang tinggi yang berpotensi menyebabkan kejadian kebocoran, peledakan,
kebakaran dan kecelakaan kerja.
Pemerintah telah mengatur K3 pressure vessel di Indonesia melalui Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Bejana Tekanan. Risiko K3 penggunaan bejana tekanan antara lain dapat disebabkan oleh
ketidaklengkapan serta tidak berfungsinya alat pengaman (safety devices) pada bejana tekanan,
penggunaan tekanan kerja melebihi tekanan maksimum yang diizinkan, kualitas bahan menurun,
cacat pada sambungan pengelasan, dan operator atau teknisi bejana tekanan yang tidak dibekali
dengan kompetensi K3.
Setiap pemakaian pressure vessel harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian (riksa uji)
K3. Riksa uji K3 pressure vessel terdiri dari riksa uji K3 pertama, berkala (sekurang-kurangnya
setiap 2 tahun sekali), dan riksa uji K3 khusus (setekah perbaikan atau kecelakaan kerja) sesuai
dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Rendahnya kualitas pelaksanaan riksa uji K3 pressure
vessel di tempat kerja serta rendahnya jaminan keamanan penggunaaan pressure vessel di tempat
kerja sehingga mempertinggi risiko peledakan dan kecelakaan kerja lainnya.
METODE
Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik yang bersifat kualitatif yang dilakukan pada
Bulan Maret sampai dengan Mei 2020. Penelitian ini membandingkan antara laporan pemeriksaan
dan pengujian K3 pressure vessel yang dilakukan oleh AK3 sepesialis PUBT di wilayah kerja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 dan tahun 2019 dengan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Permenaker) Nomor 37 Tahun 2016.
Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan unit analisis seluruh hasil pemeriksaan
dan pengujian K3 pressure vessel yang dilaporkan pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebanyak 90
Laporan. Kelengkapan dari laporan akan dibandingkan dengan persyaratan yang terdapat dalam
Permenaker No. 37 Tahun 2016 tentang K3 Bejana Tekanan dan Tangki Timbun, yang meliputi:
(1) pemeriksaan administrasi, (2) berita acara pemeriksaan dan pengujian K3, (3) data umum, (4)
gambar teknis kontruksi, (5) dokumen kalibrasi peralatan riksa uji K3, (6) pengujian tidak merusak
(Non Destructive Test), (7) pengujian kekerasan pelat, (8) pengukuran ketebalan pelat, (9) hasil
pengujian pemadatan, (10) pemeriksaan dan pengujian alat-alat pengamanan (safety devices), (11)
perhitungan ulang kekuatan konstruksi, dan (12) Surat Keterangan bejana tekanan. Kelengkapan
dari laporan pemeriksaan dan pengujian K3 pressure vessel akan dianalisis secara kualitatif.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 89
HASIL PENELITIAN
Pemeriksaan dan pengujian merupakan kegiatan mengamati, menganalisis,
membandingkan, menghitung, mengukur, pengetesan kemampuan operasi, bahan, dan konstruksi
pressure vessel untuk memastikan terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
standar yang berlaku. Pemeriksaan dan pengujian meliputi: riksa uji pertama, riksa uji berkala,
riksa uji khusus, dan riksa uji ulang. Riksa uji pertama dilakukan pada tahap perencanaan; tahap
pembuatan; saat sebelum digunakan atau belum pernah dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian;
dan saat pemasangan, perubahan, atau modifikasi. Pemeriksaan berkala dilakukan sekurang-
kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun dan pengujian dilakukan sekurang-kurangnya sekali 5 (lima)
tahun. Pemeriksaan dan pengujian khusus dilakukan setelah terjadinya kecelakaan kerja,
kebakaran, atau peledakan. Pemeriksaan dan pengujian ulang dilakukan apabila hasil pemeriksaan
dan pengujian sebelumnya terdapat keraguan.
Secara umum, pemeriksaan dan pengujian K3 pressure vessel terdiri dari beberapa tahap:
1. Pemeriksaan dokumen, gambar teknis dan administrasi;
2. Pemeriksaan persyaratan dan pengujian kelaikan K3 komponen pressure vessel;
3. Pengukuran dimensi pressure vessel;
4. Pengujian Tidak Merusak (Non Destructive Test);
5. Percobaan padat (Hydrostatic Test);
6. Perhitungan ulang kekuatan konstruksi;
Pemeriksaan dan pengujian K3 pressure vessel secara rinci meliputi:
1. Pemeriksaan dokumen, gambar teknis dan administrasi:
a. Gambar konstruksi/instalasi;
b. Sertifikat bahan dan keterangan lain;
c. Perhitungan kekuatan desain konstruksi (design calculation);
d. Catatan data pembuatan (manufacturing data record);
e. Cara kerja pressure vessel untuk bejana proses;
f. Lisensi K3 Teknisi Bejana Tekanan serta sertifikat dan buku kerja juru las;
g. Safety Data Sheet (SDS) bahan yang diisikan;
h. Register pressure vessel;
i. Riwayat perawatan pressure vessel;
j. Riwayat perbaikan pressure vessel;
k. Riwayat modifikasi pressure vessel;
l. Pemenuhan syarat-syarat K3 pada Laporan pemeriksaan dan pengujian K3 sebelumnya;
m. Data umum;
n. Data Teknik;
1) Shell / badan
2) Head / tutup
3) Pipa-pipa / channel
4) Instalasi pipa
2. Pemeriksaan persyaratan dan kelaikan K3 komponen pressure vessel, meliputi:
a. Pemeriksaan persyaratan dan kelaikan bagian utama pressure vessel, yang terdiri dari:
1) Shell/ badan
2) Head/tutup ujung
3) Jacket/selubung
4) Pipa-pipa/channel
5) Nozzle/nosel
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 90
b. Pemeriksaan persyaratan dan pengujian kelaikan safety devices pressure vessel, yang
terdiri dari:
6) Manometer (pasal 19 dan pasal 22 ayat (1));
7) Strip Merah pada tekanan kerja tertinggi manometer (pasal 22 ayat (4));
8) Pengukur Temperature (formulir 2)
9) Keran Coba (pasal 22 ayat (5));
10) Tingkap pengaman atau alat pengaman sejenis (pasal 16 ayat (1));
11) Pelat Pengaman (pasal 16 ayat (5));
12) Pipa pembuang (pasal 16 ayat (6) dan ayat (7));
13) Tanda pengenal Bejana Tekanan (nameplate / slug letter) (pasal 9 ayat (1));
14) Katup Penutup (pasal 14 ayat (1), (2), dan (4));
15) Kap Pelindung (pasal 7);
16) Ulir Penghubung (pasal 14 ayat (3));
17) Pengaman mur paking (pasal 14 ayat (5));
18) Pelindung katup (pasal 15 ayat (1));
19) Ruang bebas antara dinding bagian dalam dengan bagian katup penutup > 3 mm
(pasal 15 ayat (2));
20) Lubang pelindung katup (pasal 15 ayat (3);
21) Mur-mur penutup atau sumbat penutup berulir, untuk Lubang penutup katup (pasal
15 ayat (4));
22) Massa Kerenik (porous mass) (pasal 13 ayat (1));
23) Alat untuk menentukan berat gas yang diisikan (pasal 17 ayat (1));
24) Alat pembuang gas (pasal 17 ayat (3));
25) Alat anti guling (pasal 18 ayat (1) dan ayat (2));
26) Regulator penurun tekanan (pasal 19);
27) Warna (pasal 21);
28) Register Bejana Tekanan (pasal 10);
29) Label Bejana Penyimpanan Gas (lampiran);
c. Pemeriksaan persyaratan dan kelaikan support pressure vessel;
d. Pemeriksaan persyaratan dan kelaikan Instalasi Pipa pressure vessel;
e. Penimbangan berat (untuk pressure vessel dengan volume sampai dengan 60 liter)
3. Pengukuran Dimensi pressure vessel, yang terdiri atas:
a. Shell/ badan
b. Head/tutup ujung
c. Pipa-pipa/channel
d. Instalasi Pipa
e. Nozzle/nosel
4. Pengujian tidak merusak / Non Destructive Test (NDT), terdiri dari: pemeriksaan dan
pengujian kualitas las-lasan, pengujian nilai kekerasan pelat (hardness test), dan pengukuran
ketebalan pelat (wall thickness test). Kesemuanya dilakukan pada komponen:
a. Shell / badan
b. Head / tutup
c. Pipa-pipa/channel
d. Nozzle/nosel
e. Instalasi Pipa
5. Percobaan padat (hydrostatic test)
6. Perhitungan ulang kekuatan konstruksi (re-calculation pressure vessel);
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 91
Rekapitulasi kegiatan pemeriksaan dan pengujian K3 pressure vessel berdasarkan Surat
Keputusan Penunjukan (SKP) AK3 PUBT di Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(PJK3) dan berdasarkan jenis pemeriksaan pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.
Rekapitulasi Pemeriksaan dan Pengujian K3 Pressure Vessel oleh AK3 PUBT Berdasarkan
Jenis Pemeriksaan di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2019
No. SKP AK3
PUBT
Jumlah kegiatan riksa uji K3 pressure vessel
Ket Pertama
Berkala Khusus Ulang Perencanaan Pembuatan Sebelum
digunakan
Pemasangan /
perubahan
1 PJK3 PT. A 3 40
2 PJK3 PT. B 3
3 PJK3 PT. C 2
4 PJK3 PT. D 1 5 PJK3 PT. E 1
Total 4 46
Rekapitulasi kegiatan pemeriksaan dan pengujian K3 pressure vessel berdasarkan Surat
Keputusan Penunjukan (SKP) AK3 PUBT di Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(PJK3) dan berdasarkan jenis pemeriksaan pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.
Rekapitulasi Pemeriksaan dan Pengujian K3 Pressure Vessel oleh AK3 PUBT
Berdasarkan Jenis Pemeriksaan di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2018
No. SKP AK3
PUBT
Jumlah kegiatan riksa uji K3 pressure vessel
Ket Pertama
Berkala Khusus Ulang Perencanaan Pembuatan Sebelum
digunakan
Pemasangan /
perubahan
1 PJK3 PT. A 1 24
2 PJK3 PT. B 7 3 PJK3 PT. C 4
4 PJK3 PT. D 3
5 PJK3 PT. E 1
Total 1 39
Dari tabel 1 dan 2 di atas, jumlah kegiatan pemeriksaan dan pengujian K3 pressure vessel
berdasarkan jenis pemeriksaan didominasi oleh pemeriksaan dan pengujian K3 berkala yaitu
sejumlah 46 kegiatan pada tahun 2019 dan 39 kegiatan pada tahun 2018. Sedangkan pemeriksaan
dan pengujian K3 pertama pada tahap sebelum digunakan 4 kegiatan pada tahun 2019 dan 1
kegiatan pada tahun 2018.
Rekapitulasi kegiatan pemeriksaan dan pengujian K3 pressure vessel berdasarkan Surat
Keputusan Penunjukan (SKP) AK3 PUBT di Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(PJK3) dan berdasarkan jenis pressure vessel pada Tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dilihat pada
tabel berikut:
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 92
Tabel 3.
Rekapitulasi Pemeriksaan dan Pengujian K3 Pressure Vessel oleh AK3 PUBT
Berdasarkan Jenis Pressure Vessel di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2019
No. SKP AK3
PUBT
Jumlah kegiatan riksa uji K3 pressure vessel
2018 2019
Air Receiver
Tank
Bejana Transport
Bejana Proses
Botol Baja
Botol LPG
Air Receiver
Tank
Bejana Transpo
rt
Bejana
Proses
Botol Baja
Botol LPG
1 PJK3 PT. A 25 43
2 PJK3 PT. B 7 3
3 PJK3 PT. C 4 2
4 PJK3 PT. D 3 1 5 PJK3 PT. E 1 1
Total 39 1 49 1
Dari tabel 3 di atas, jumlah kegiatan pemeriksaan dan pengujian K3 pressure vessel
berdasarkan jenis pressure vessel didominasi oleh pemeriksaan dan pengujian K3 jenis air receiver
tank yaitu sejumlah 49 unit pada tahun 2019 dan 39 unit pada tahun 2018. Sedangkan pemeriksaan
dan pengujian K3 jenis LPG 1 kegiatan pada tahun 2019 dan 1 kegiatan pada tahun 2018.
Rekapitulasi pemenuhan persyaratan pemeriksaan dan pengujian K3 pressure vessel
berdasarkan Permenaker No. 37 Tahun 2016, dari kegiatan pemeriksaan dan pengujian AK3 bidang
PUBT yang dilaporkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 dan tahun 2019
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.
Rekapitulasi Pemenuhan Syarat Pemeriksaan dan Pengujian K3 Pressure Vessel oleh AK3
PUBT Berdasarkan Permenaker No. 37 Tahun 2016 di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2019
No Syarat Riksa Uji
Pemenuhan dari total kegiatan Riksa Uji*
Catatan AK3 A
n =68
AK3 B
n = 10
AK3 C
n = 6
AK3 D
n = 4
AK3 E
n = 2
1 Pemeriksaan dokumen,
gambar teknis dan
administrasi;
a. Gambar konstruksi/instalasi; 50% 0% 0% 100% 0%
Kaidah gambar
teknik
b. Sertifikat bahan dan keterangan lain;
50% 50% 50% 50% 50% Keabsahan
c. Perhitungan kekuatan desain
konstruksi (design
calculation);
0% 0% 0% 0% 0%
d. Catatan data pembuatan
(manufacturing data record); 0% 0% 0% 0% 0%
e. Cara kerja untuk bejana
proses; NA** NA NA NA NA
Tidak ada Laporan
untuk Bejana Proses
f. Lisensi K3 Teknisi Bejana
Tekanan dan juru las; 75% 0% 50% 100% 100%
Penyebutan Lisensi
K3 Bejana Tekan
g. Safety Data Sheet (SDS) bahan yang diisikan; 0% NA NA 0% 0%
Beberapa jenis media isi hanya
udara
h. Register bejana tekanan; 0% 0% 0% 0% 0%
i. Riwayat perawatan bejana tekanan;
0% 0% 0% 0% 0%
j. Riwayat perbaikan bejana
tekanan; 0% 0% 0% 0% 0%
k. Riwayat modifikasi bejana tekanan;
0% 0% 0% 0% 0%
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 93
l. Pemenuhan syarat-syarat K3 pada Laporan pemeriksaan
dan pengujian K3
sebelumnya;
100% 100% 100% 100% 100% Cross check tindak lanjut dan bukti di
lapangan
m. Data umum; 100% 100% 100% 100% 100% Kelengkapan Data n. Data Teknik;
1) shell / badan 100% 100% 100% 100% 100% Kelengkapan Data
2) head / tutup 100% 100% 100% 100% 100% Kelengkapan Data
3) Pipa-pipa/channel 0% 0% 0% 0% NA 4) Instalasi pipa 0% 0% 0% 0% NA
2 Pemeriksaan persyaratan dan
kelaikan K3 komponen
pressure vessel, meliputi:
a Bagian utama pressure vessel,
yang terdiri dari:
a. Shell/ badan 100% 100% 100% 100% 100% Tatacara riksa
b. Head/tutup ujung 100% 100% 100% 100% 100% Tatacara riksa c. Jacket/selubung 100% 100% 100% 100% 100% Tatacara riksa
d. Pipa-pipa/channel 0% 0% 0% 0% 0%
e. Nozzle/nosel 0% 0% 0% 0% 0%
b Pemeriksaan persyaratan dan
pengujian kelaikan Safety
devices pressure vessel, yang
terdiri dari:
Manometer (pasal 19 dan pasal
22 ayat (1)); 100% 100% 100% 100% 100% Tatacara riksa uji
Strip merah pada tekanan kerja
tertinggi manometer (pasal 22 ayat (4));
100% 100% 100% 100% 100%
Kesesuaian dengan
Maximum Allowable Working
Pressure (MAWP)
Pengukur temperature (formulir
2); 100% 0% 0% 100% 0%
Keran Coba (pasal 22 ayat (5)); 0% 0% 0% 0% 0%
Tingkap pengaman atau alat
pengaman sejenis (pasal 16 ayat
(1));
100% 100% 100% 100% 100% Tatacara riksa uji
Pelat pengaman (pasal 16 ayat
(5)); NA NA NA NA NA Not Applicable
Pipa pembuang (pasal 16 ayat
(6) dan ayat (7)); 0% 0% 0% 0% 0%
Tanda pengenal Bejana Tekanan
(nameplate / slug letter) (pasal 9
ayat (1));
100% 100% 100% 100% 100% tindak lanjut
Katup penutup (pasal 14 ayat (1), (2), dan (4));
0% 0% 0% 0% 0%
Kap pelindung (pasal 7); NA NA NA NA NA Not Applicable
Ulir penghubung (pasal 14 ayat
(3)); NA NA NA NA NA Not Applicable
Pengaman mur paking (pasal 14
ayat (5)); NA NA NA NA NA Not Applicable
Pelindung katup (pasal 15 ayat
(1)); NA NA NA NA NA Not Applicable
Ruang bebas antara dinding
bagian dalam dengan bagian
katup penutup > 3 mm (pasal 15
ayat (2));
NA NA NA NA NA Not Applicable
Lubang pelindung katup (pasal
15 ayat (3); NA NA NA NA NA Not Applicable
Mur-mur penutup atau sumbat penutup berulir, untuk Lubang
penutup katup (pasal 15 ayat
(4));
NA NA NA NA NA Not Applicable
Massa kerenik (Porous Mass) (pasal 13 ayat (1));
NA NA NA NA NA Not Applicable
Alat untuk menentukan berat gas NA NA NA NA NA Not Applicable
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 94
yang diisikan (pasal 17 ayat (1));
Alat pembuang gas (pasal 17
ayat (3)); NA NA NA NA 0%
Alat anti guling (pasal 18 ayat
(1) dan ayat (2)); 100% 0% 0% 0% 0%
Regulator penurun tekanan
(pasal 19); NA NA NA NA NA Not Applicable
Warna (pasal 21); 0% 0% 0% 0% 0%
Register bejana tekanan (pasal 10);
0% 0% 0% 0% 0%
Label bejana penyimpanan gas
(Lampiran); 0% 0% 0% 0% 0%
c Pemeriksaan persyaratan dan
kelaikan Support Pressure
vessel;
100% 100% 100% 100% 100% Tatacara riksa uji
d Pemeriksaan persyaratan dan
kelaikan Instalasi Pipa Pressure vessel;
100% 100% 100% 100% 100% Tatacara riksa uji
e Penimbangan berat (untuk
pressure vessel dengan volume
sampai dengan 60 liter);
NA NA NA NA 100% Tatacara
penimbangan
3 Pengukuran Dimensi Pressure
vessel, yang terdiri atas:
a. Shell/ badan 100% 100% 100% 100% 100% Tatacara riksa
b. Head/tutup ujung 100% 100% 100% 100% 100% Tatacara riksa c. Pipa-pipa/channel 0% 0% 0% 0% 0%
d. Instalasi Pipa 0% 0% 0% 0% 0%
e. Nozzle/nosel 0% 0% 0% 0% 0%
4 Pengujian tidak merusak /
Non Destructive Test (NDT),
terdiri dari: Pemeriksaan dan
pengujian Kualitas Las-lasan, Pengujian Kekerasan Pelat
(Hardness Test), dan
Pengukuran Ketebalan Pelat
(Wall Thickness Test) pada komponen:
a. Shell / badan 50% 0% 33% 50% 0% Jenis NDT
b. Head / tutup 50% 0% 33% 50% 0%
c. Pipa-pipa/channel 0% 0% 0% 0% 0% d. Nozzle/nosel 0% 0% 0% 0% 0%
e. Instalasi Pipa 0% 0% 0% 0% 0%
5 Percobaan padat (hydrostatic
test) 50% 0% 33% 50% 100% Tekanan uji
6 Perhitungan ulang kekuatan
konstruksi (re-calculation
Pressure vessel) 75% 0% 100% 50% 100%
Kesesuaian
formula dan standar
perhitungan
* % pemenuhan dihitung berdasarkan total kegiatan riksa uji K3 pressure vessel yang dilakukan
oleh AK3
** NA: Not Applicable
Seluruh laporan telah dilengkapi dengan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) AK3 PUBT
dan SKP Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) bidang pemeriksaan dan
pengujian teknik PUBT dari Kementerian Ketenagakerjaan R.I. dan masih dalam masa berlaku.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 95
Berdasarkan tabel 4 di atas, diketahui syarat-syarat pemeriksaan dan pengujian K3
pressure vessel yang telah memenuhi Permenaker No. 37 Tahun 2016 dengan tingkat pemenuhan
100% antara lain:
1. Pemeriksaan Data Umum;
2. Pemeriksaan Data Teknik;
a. Shell / badan
b. Head / tutup
3. Pemeriksaan persyaratan dan kelaikan K3:
a. Shell / badan
b. Head / tutup
c. Selubung / jacket
4. Pemeriksaan persyaratan dan pengujian kelaikan safety devices
a. Manometer (pasal 19 dan pasal 22 ayat (1));
b. Strip merah pada tekanan kerja tertinggi manometer (pasal 22 ayat (4));
c. Tingkap pengaman atau alat pengaman sejenis (pasal 16 ayat (1));
d. Tanda pengenal Bejana Tekanan (nameplate / slug letter) (pasal 9 ayat (1));
5. Pemeriksaan persyaratan dan kelaikan support;
6. Pemeriksaan persyaratan dan kelaikan instalasi pipa;
7. Penimbangan berat (untuk pressure vessel dengan volume sampai dengan 60 liter);
8. Pengukuran dimensi
a. Shell / badan
b. Head / tutup
9. SKP AK3 PUBT dari Kemenaker R.I. dan masih dalam masa berlaku
10. SPK PJK3 bidang pemeriksaan dan pengujian teknik PUBT dari Kemenaker R.I. dan
masih dalam masa berlaku
Syarat-syarat pemeriksaan dan pengujian K3 pressure vessel yang sebagian telah
memenuhi Permenaker No. 37 Tahun 2016 antara lain:
1. Pemeriksaan gambar konstruksi / instalasi, tingkat pemenuhan: 58%, yang belum
memenuhi: 42%
2. Pemeriksaan sertifikat bahan dan keterangan lainnya, tingkat pemenuhan: 50%, yang
belum memenuhi: 50%
3. Pemeriksaan lisensi K3 teknisi dan juru las, tingkat pemenuhan: 33%, yang belum
memenuhi: 67%.
4. Pemeriksaan persyaratan dan pengujian kelaikan safety devices:
a. Pengukur temperature, tingkat pemenuhan: 20%, yang belum memenuhi: 80%
b. Alat anti guling, tingkat pemenuhan: 62%, yang belum memenuhi: 38%
5. Pengujian tidak merusak / Non Destructive Test (NDT):
a. Badan / shell, tingkat pemenuhan: 58%, yang belum memenuhi: 42%
b. Tutup / head, tingkat pemenuhan: 58%, yang belum memenuhi: 42%
6. Percobaan pemadatan (hydrostatic test), tingkat pemenuhan: 56%, yang belum memenuhi:
44%
7. Perhitungan ulang kekuatan konstruksi (re-calculation), tingkat pemenuhan: 32%, yang
belum memenuhi: 68%
Syarat-syarat pemeriksaan dan pengujian K3 pressure vessel yang belum memenuhi
Permenaker No. 37 Tahun 2016 antara lain:
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 96
1. Perhitungan kekuatan desain konstruksi (design calculation);
2. Register pressure vessel;
3. Riwayat perawatan pressure vessel;
4. Riwayat perbaikan (termasuk pergantian spare part) pressure vessel; dan
5. Riwayat modifikasi pressure vessel;
6. Pemenuhan syarat-syarat K3 pada Laporan pemeriksaan dan pengujian K3 sebelumnya;
7. Pemeriksaan Data Teknik;
a. Pipa-pipa / channel
b. Instalasi pipa
8. Pemeriksaan persyaratan dan kelaikan K3:
a. Pipa-pipa / channel
b. Nosel / nozzle
9. Pemeriksaan persyaratan dan pengujian kelaikan safety devices
a. Keran coba
b. Pipa pembuangan
c. Katup penutup
d. Alat pembuang gas
e. Pewarnaan
f. Register pressure vessel
g. Label
10. Pengukuran dimensi
a. Pipa-pipa / channel
b. Instalasi pipa
c. Nosel / nozzle
11. Pengujian tidak merusak / Non Destructive Test (NDT):
a. Pipa-pipa / channel
b. Nosel / nozzle
c. Instalasi pipa
PEMBAHASAN
Data umum berisikan informasi tentang pemilik, alamat, pemakai, lokasi unit, nama
operator, jenis bejana, pabrik pembuat, merk/type, tahun pembuatan, nomor seri, tekanan kerja
maksimum yang diperbolehkan (Maximum Allowable Working Pressure / MAWP), kapasitas,
media yang digunakan, temperature kerja, standar yang dipakai, digunakan untuk, tanggal
pemeriksaan dan pengujian, lokasi pemeriksaan dan pengujian. Pemilik pressure vessel seringkali
berbeda dengan pemakai, sebagai contoh air receiver tank untuk nitrogen yang dipinjamkan dan
dipasok dari luar daerah untuk disewa oleh pemakai (konsumen). Contoh lainnya: adalah botol
LPG yang merupakan milik PT. Pertamina direparasi oleh perusahaan repair LPG untuk
selanjutnya disalurkan kembali kepada agen pengisi LPG dan masyarakat. Lokasi unit diisikan
keterangan di unit serta perusahaan mana pressure vessel tersebut ditempatkan dan digunakan.
Nama operator diisikan tentang identitas seluruh tenaga kerja yang sehari-hari mengoperasikan,
mengisi, membersikan, melakukan perawatan serta perbaikan terhadap pressure vessel pada
seluruh shift kerja. Selanjutnya pada bagian ini juga dimasukan keterangan tentang pekerja yang
telah dilengkapi dengan seritifikasi K3 teknisi bejana tekanan dari Kemenaker R.I. dan tenaga kerja
yang belum dilengkapi dengan sertifikat. Pada bagian jenis bejana tekanan dituliskan mengenai
jenis pressure vessel yang diriksa uji yang antara lain terdiri dari: Air Receiver Tank, bejana
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 97
transport, bejana proses, botol baja, botol LPG, dan sebagainya. Pabrik pembuat diisikan data
mengenai perusahaan yang membuat pressure vessel. Begitu juga pada maisng-masing bagian
merk/type, tahun pembuatan dan nomor seri. Merk pada produsen tertentu biasanya memiliki type-
type yang berbeda-beda. Begitu juga dengan nomor seri, digunakan untuk membedakan identitas
antar produk yang satu dengan yang lainnya untuk merk dan type yang sama. Untuk itu, nomor seri
setiap produk akan berbeda dengan produk lainnya, walaupun perusahaan pembuat, merk, dan
typenya sama.2
Tekanan kerja maksimum yang diperbolehkan (Maximum Allowable Working Pressure /
MAWP) adalah tekanan internal dimana bagian terlemah dari bejana tekan dibebani hingga batas
kemampuannya. Tekanan operasi atau tekanan kerja (working pressure) adalah tekanan yang
diperlukan untuk proses produksi, yang dilayani oleh suatu bejana tekan yang dioperasikan pada
tekanan tersebut. Tekanan desain adalah tekanan yang digunakan untuk mendesain suatu bejana
tekan, biasanya memiliki beda tekanan sekitar 10% atau 30 psi dengan tekanan kerja. 3
Tekanan
kerja maksimum yang diperbolehkan (Maximum Allowable Working Pressure / MAWP) untuk
suatu pressure vessel dapat dilihat dari spesifikasi peralatan dan riwayat laporan pemeriksaan
pengujian K3 sebelumya. Tekanan kerja maksimum yang diperbolehkan (Maximum Allowable
Working Pressure / MAWP) ditentukan oleh pemakai, diawasi oleh AK3 spesialis PUBT, dan
ditetapkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 PUBT yang ada di instansi
ketenagakerjaan setempat dengan memperhatikan tekanan desain. Tekanan kerja maksimum yang
diperbolehkan (Maximum Allowable Working Pressure / MAWP) ditetapkan maksimum 96% dari
desain pressure. Sisa 4% digunakan sebagai safety range untuk fungsi / kerja alat pengaman (safety
devices) berupa tingkap pengaman / safety valve / Pressure Safety Valve (PSV). Apabila safety
devices tingkap pengaman tidak bekerja, maka tenaga kerja yang mengoperasikan bejana tekanan
harus sigap mengangkat tuas safety valve atau mengentikan pressure.4
Penggunaan satuan yang digunakan pada dokumen pabrik pembuat maupun spesifikasi
peralatan dan riwayat laporan pemeriksaan pengujian K3 sebelumya perlu diperhatikan. Satuan
tekanan yang sering digunakan di lapangan adalah bar, sedangkan dalam Permenaker Nomor 37
Tahun 2016 mengunakan satuan kg/cm2. Satuan internasional untuk tekanan adalah pascal atau
newton per meter persegi (N/m2). 1 bar = 1,02 kg/cm
2 = 100.000 pascal.
5 Pekerja seringkali
menganggap sama antara bar dan kg/cm2. Hal ini tentunya akan menimbulkan potensi bahaya
bilamana terdapat kesalahan pembacaan nilai satuan dari safety devices pada pressure vessel.
‗Kapasitas‘ pressure vessel diisikan informasi tentang daya tampung atau volume dari
pressure vessel dalam satuan liter. Apabila tidak terdapat pada spesifikasi peralatan, maka AK3
PUBT harus menghitung berapa volume dari pressure vessel berdasarkan dari hasil pengukuran
dimensi. ‗Media yang digunakan‘, dituliskan informasi tentang jenis bahan atau gas yang
dimasukan dalam pressure vessel. Hal ini penting untuk mengetahui karakteristik bahan, sifat
kimia, sifat fisika, jenis potensi bahaya, penentuan tindakan pengamanan terhadap pressure vessel.
‗Temperatur kerja‘ dituliskan informasi tentang suhu kerja normal atau suhu kerja rata-rata pada
keadaan normal dari operasional pressure vessel. Hal ini digunakan sebagai acuan untuk
menentukan temperature kerja aman pada pressure vessel berdasarkan spesifikasi dari pabrik
pembuat, peraturan, dan standar. ‗Standar yang digunakan‘, diisikan informasi tentang standar yang
digunakan oleh pabrik pembuat dan pemakai pressure vessel dalam design pembuatan dan
pengamanan pressure vessel, antara lain: American Society of Mechanical Enginer (ASME) Code
VIII, British Standard (BS), Japanese Industrial Standard (JIS) B 8265, Standar Nasional
Indonesia (SNI) 1452:2011 tentang Tabung Baja LPG, American Petrolium Institute (API) 510
(Pressure Vessel Inspection Codes)6 dan sebagainya. Kolom ‗digunakan untuk‘, diisi informasi
tentang penggunaan pressure vessel di tempat kerja digunakan untuk keperluan apa. Sedangkan
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 98
untuk kolom ‗tanggal pemeriksaan dan pengujian‘, ‗lokasi pemeriksaan dan pengujian‘, diisikan
informasi tentang tanggal pelaksanaan dan lokasi dimana pemeriksaan dan pengujian K3 pressure
vessel dilakukan.
Data teknik terdiri dari data teknik untuk bagian shell / badan, bagian head / tutup, pipa-
pipa/channel, dan Instalasi pipa. Bagian shell / badan pressure vessel baik itu head kiri atau head
kanan, ataupun head atas dan head bawah, data teknik yang harus diisikan terdiri dari jumlah
roundshell, cara penyambungan, material/bahan, diameter dalam (inside diameter), ketebalan,
panjang badan, jenis penguat, jumlah penguat, dan ukuran/dimensi penguat. Bagian head / tutup
pressure vessel, data teknik yang diisikan terdiri dari jenis/bentuk, jari-jari lengkungan (R), jari-jari
lekukan (r), kemiringan, ketebalan, material/bahan. Bagian pipa-pipa (channel), data teknik yang
harus diisikan adalah jenis/bentuk, dimensi untuk diameter, ketebalan, panjang, jumlah, material,
dan cara pemasangan. Bagian instalasi pipa, data teknik yang harus diisikan adalah diameter,
ketebalan, jenis katup, jumlah. Data teknik dapat diperoleh dari data di lapangan. Data teknik
sangat bermanfaat untuk acuan pada tahapan pemeriksaan dan pengujian K3 pressure vessel
berikutnya, seperti pada tahap Non Destructive Test (NDT), acuan pengukuran dimensi dan acuan
perbandingan dalam melakukan perhitungan kekuatan konstruksi. Tanpa data teknik yang cukup,
maka dapat menghambat pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian K3 pressure vessel berikutnya.
Bahan adalah benda yang dengan sifat-sifatnya yang khas dimanfaatkan dalam bangunan,
mesin, peralatan atau produk. Bahan terdiri dari: logam, bahan campuran, dan bukan logam.
Terkait dengan material / bahan, berdasarkan pasal 8 Permenaker No. 37 tahun 2016, dijelaskan
bahwa: bahan dan konstruksi Bejana Tekanan harus cukup kuat. Paduan logam (metal alloys)
dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu paduan besi (Ferrous) dan paduan bukan besi
(Nonferrous). Ferrous (logam ferro) terdiri dari steel dan cast iron. Paduan besi adalah paduan yang
unsur utamanya adalah besi termasuk baja dan besi cor. Sedangkan paduan bukan besi adalah
paduan selain besi.7 Besi yang kimiawi murni (Ferrum, Fe) tidak cocok sebagai bahan, karena
terlalu lunak. Besi yang dapat diolah secara teknis selalu merupakan suatu paduan antara besi (Fe)
dengan zat arang (C) dan unsur-unsur lainnya. Ukuran yang menentukan untuk kekerasan,
kekuatan, dan keuletan ialah tinggi kadar zat arang yang selalu ada di dalam besi.8 Material baja
merupakan perpaduan antara besi dengan karbon yang komposisinya bervariasi, tergantung jenis
material baja, dengan kisaran antara 0,1% sampai dengan 1,5%. Fungsi unsur karbon dalam baja
adalah sebagai komponen pengeras yang mencegah pergeseran kisi kristal dari atom besi. Selain
karbon, unsur paduan lain yang terdapat dalam material baja antara lain: mangan (Mn) berfungsi
untuk meningkatkan kekuatan dan kekerasan pada material baja serta untuk menurunkan laju
pendinginan sehingga material baja lebih tahan lama terhadap abrasi, silikon (Si) berfungsi untuk
meningkatkan elastisitas material baja, kromium (Cr) berfungsi untuk meningkatkan ketahanan
material baja terhadap korosi serta untuk meningkatkan kekerasan baja kuat tarik dan ketahanan
terhadap abrasi, vanadium (V) berfungsi untuk menaikkan kekuatan tarik dan batas mulur. Material
baja memiliki komposisi kandungan logam yang bervariasi sehingga muncul beberapa istilah untuk
membedakan jenis material baja yang ada.9 Kegunaan baja sangat bergantung pada sifat-sifat baja
yang sangat bervariasi yang diperoleh dari pemaduan dan penerapan proses perlakuan panas. Sifat
mekanik dari baja sangat tergantung pada struktur mikronya, sedangkan struktur mikro sangat
mudah dirubah melalui proses pelakukan panas.10
Sebaiknya pressure vessel menggunakan
material jenis baja karbon rendah. Material yang banyak digunakan untuk pembuatan bejana tekan
adalah SA-516 Gr 70.11
Identitas dari jenis material dapat diketahui dari sertifikat bahan (mill certificate). Sertifikat
bahan dan keterangan lain yang dilaporkan harus disertai dengan cap yang sah dari third party dan
pemasok material. Untuk itu, setiap pelat atau pipa pressure vessel harus dilengkapi dengan
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 99
sertifikat bahan. Pada sertifikat bahan tersebut pada umumnya tertera dimensi, breaking strength,
yield point (batas mulur), regangan dan komposisi kimia. Jika pelat atau pipa pada pressure vessel
tidak dilengkapi dengan sertifikat bahan, maka harus diujikan ke laboratorium pengujian logam
yang diakui Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan R.I..12
Pemeriksaan persyaratan dan kelaikan K3 pada bagian shell, head, dan jacket antara lain
menilai kondisi fisik dari masing-masing bagian tersebut apakah ada kerusakan, cacat, dan korosi.
Begitu juga untuk bagian pipa-pipa dan instalasi pipa, perlu diperhatikan kedudukan pipa, dimensi
ukuran sebagaimana gambar rencana, gerakan-gerakan akibat pengembangan dan atau pengerutan
akibat temperature, dan tegangan-tegangan yang mungkin terjadi akibat pengelasan atau pemuaian
akibat panas pada pipa dan beban-beban yang ditanggung pipa.13
Pengetesan yang dilakukan pada
pipa antara lain kekuatan, kebocoran, ketelitian dan kesempurnaan dalam pengelasan pipa. Hal-hal
yang perlu diperhatikan dalam pengetesan pipa antara lain, (1) mechanical equipment, yaitu pump,
compressor, LPG loading arm dipisahkan dari pengetesan dengan memasang blind flanges, (2)
untuk alat-alat instrument (rupture discs, relief valve, flow nozzles, dan lain-lain) dilakukan
pengetesan terpisah, dan selama pengetesan pipa dapat dipisahkan dengan menggunakan block
valve, (3) control globe valve juga dipisahkan dari pengetesan pipa dengan cara menggunakan
spool sementara yaitu setelah menutup dengan blind flange pada bagian depan dan belakang dari
globe valve, sehingga pengetesan akan melalui spool atau bypass sebagai penghubung aliran dari
bahan untuk pengetesan. Pneumatic test menggunakan udara atau gas nitrogen yang disuplai dari
kompresor. Tekanan awal yang diberikan adalah 1,5 kg/cm2 dan dipertahankan dalam jangka
waktu tertentu untuk mendapatkan strain yang sama pada pipa. Semua sambungan dapat diperiksa
dari kebocoran dengan menggunakan cairan yang dapat berbusa. Tekanan ditambah secara
bertahap sebesar ± 10% dari tekanan terakhir hingga mencapai pressure test yang dipersyaratkan
dan dipertahankan dalam jangka waktu tertentu.14
Korosi pada logam secara umum timbul sebagai hasil reaksi elektrokimia yang diakibatkan
oleh adanya elektrolit-elektrolit yang bersentuhan dengan permukaan logam. Elektrolit tersebut
biasanya berbentuk larutan garam asam atau alkali. Berdasarkan hal ini, maka type korosi yang
terjadi dinamakan type korosi basah. Sedangkan type korosi yang dihasilkan dari reaksi kimia
antara logam dan cairan atau gas yang bukan elektrolit diklasifikasi sebagai type korosi kering.15
Pressure vessel yang mengalami aging, lebih berisiko terhadap semua jenis kerusakan, maka perlu
dilakukan jenis analisa kelayakan tertentu untuk memastikan kemampuan dan kelayakan alat
tersebut.16
Teknik dan prosedur pengelasan yang tidak baik menimbulkan cacat pada las yang
menyebabkan diskontinuitas dalam las. Cacat yang umumnya dijumpai adalah: peleburan tidak
sempurna, penetrasi kampuh yang tidak memadai, porositas, peleburan berlebihan, masuknya terak,
dan retak-retak. Welding Inspection adalah kegiatan inspeksi yang mengkhususkan pada
pengendalian dan pemastian mutu sambungan las berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan.
Inspeksi las menitikberatkan pada aspek keselamatan personil, struktural dan operasional yang
berkaitan dengan pengelasan. Inspektor las berwenang untuk mereview WPS (spesifikasi prosedur
las atau SPL) dan PGR (rekaman kualifikasi prosedur atau RKP) untuk meyakinkan bahwa WPS
tersebut mewakili pekerjaan las dari pembuatan, perakitan, atau perbaikan dari pressure vessel, dan
apakah PQR yang dilampirkan benar-benar mendukung WPS tadi.17
Kualitas hasil pengesalan
ditentukan oleh beberapa faktor antara lain: teknik pengelasan, bahan logam yang disambung,
pengaruh panas, serta jenis kampuh yang tepat.18
Risk Based Inspection (RBI) merupakan sebuah
metode untuk merencanakan pemeriksaan peralatan statis yang berdasarkan risiko yang dimiliki
oleh suatu peralatan produksi. Kegiatan inspeksi, pengamatan, dan pemeriksaan diperlukan untuk
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 100
memastikan kesiapan kondisi operasi. Hal ini adalah untuk memastikan keselamatan kerja,
produktivitas, dan keuntungan operasi.19
Dalam merancang bejana tekan, tahap awal yang dilakukan adalah mendefinisikan fungsi
dari bejana tekan tersebut dan juga kapasitas operasi bejana tekan. Fungsi dan kapasitas akan
menentukan dimensi awal dari bejana tekan, ditambah dengan tekanan kerjanya, akan dapat
menentukan tebal pelat minimal yang akan digunakan untuk konstruksi bejana tekan. Ketebalan
pelat bejana tekan di pasaran adalah 3 inch pada bagian shell dan head. Bagian-bagian kritis dari
bejana tekan seperti nozzle, dan persambungan antara shell dan head perlu mendapatkan perhatian
khusus, agar konsentrasi tegangan dan diskontinuitas tegangan yang terjadi tidak mengakibatkan
kegagalan pada struktur.20
Pemeriksaan dan pengujian K3 oleh AK3 spesialis PUBT yang ada di Perusahaan Jasa
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3), maka baik AK3 spesialis PUBT maupun PJK3 harus
dilengkapi dengan Surat Keputusan Penunjukan (PJK3) dari Kementerian Ketenagakerjaan R.I. dan
harus masih dalam masa berlaku. SKP PJK3 yang dimaksud adalah SPK PJK3 untuk jasa
pemeriksaan dan pengujian teknik bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan (PUBT).21
Uji Tanpa Merusak (Non Destructive Test / NDT) adalah sarana penunjang yang sangat
diandalkan oleh kegiatan pengendalian dan pemastian mutu las sebagai sarana untuk mendapatkan
data dari ukuran/dimensi objek inspeksi maupun jenis jenis, bentuk, dan lokasi non konformasi
yang terdapat pada sambungan las. Adapun jenis-jenis NDT adalah sebagai berikut: Dye/liquid
penetration, Magnetic particle, Radiografi, Ultrasonic, Eddy current, Electro magnetic sorting,
Neutron radiografi, Optical dan acoustic holografi, Acoustic emission, Microwave inspection,
Hardness test, Leaktest, Spark test, Chemical spot check.22
Pengujian Tidak Merusak (Non Destructive Test) yang dilakukan pada beberapa AK3, hanya
terbatas pada pengukuran ketebalan pelat (wall thikness test), sedangkan untuk pengujian las-lasan
dan pengukuran kekerasan pelat (hardness test) masih jarang dilakukan. Selain itu, laporan
kalibrasi alat ukur masih jarang dilakukan. Non Destructive Test (NDT) merupakan sarana
penunjang yang sangat diandalkan dalam kegiatan pengendalian dan pemastian mutu, untuk
mengungkapkan jenis-jenis non konformasi (cacat) pada benda objek inspeksi. setelah cacat (non
konformasi) tersebut diketahui cacat tersebut dapat diperbaiki, sehingga menghasilkan permukaan
benda objek inspeksi yang bebas cacat, sekaligus mencegah terjadinya perkembangan cacat
tersebut menjadi penyebab kerusakan yang lebih serius. Secara umum, NDT terdiri dari beberapa
metode, antara lain: Dye Penetrant Test (DPT), Magnetic Particle Test (MPT), Ultrasonic Test
(UT), ataupun Radiography Test (RT).
Pengujian Hardness test digunakan untuk mengetahui nilai kekerasan pelat. Kekerasan
merupakan ukuran ketahanan material terhadap deformasi plastis terlokalisasi. Pengujian kekerasan
merupakan teknik untuk mengetahui sifat mekanik dari suatu material yang paling sering
digunakan, dengan alasan (1) sederhana dan relative murah, tidak memerlukan persiapan specimen
yang khusus dan alatnya relatif murah, serta (2) sifat mekanik lain-seperti kekuatan tarik- dapat
diperkirakan dari nilai kekerasan.Terdapat berbagai metode pengujian kekerasan, seperti Brinell,
Vickers, dan Rockwell. Pada metode pengujian kekerasan, umumnya digunakan indentor kecil
(berbentuk bola atau pyramid) yang ditekan ke permukaan bahan dengan mengontrol besar beban
dan laju pembebanan. 23
Nilai Hardness test digunakan untuk menentukan kuat Tarik material yang
merupakan bagian dari perhitungan ulang kekuatan konstruksi (recalculation) dibandingkan
dengan dengan tekanan kerja dan ketebalan pelat (hasil wall thickness) secara aktual.
Beberapa catatan untuk persyaratan riksa uji yang telah dilaporkan antara lain adalah
pemenuhan kaidah dan persyaratan dalam pembuatan gambar teknis untuk gambar
konstruksi/gambar instalasi, diantaranya: pencantuman skala, border huruf dan angka,
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 101
pencantuman legend, detail dimensi/ukuran, detail material, dan detail las-lasan. Lisensi K3
Teknisi Bejana Tekanan merupakan nomenklatur baru terkait dengan kewenangan petugas yang
berkaitan dengan operasional dan perawatan pressure vessel. Selain itu, juru las yang melakukan
pekerjaan pengelasan pada pressure vessel harus dilengkapi dengan sertifikat kualifikasi juru las di
tempat kerja dan buku kerja untuk melihat aktivitas welding dalam 6 (enam) bulan terakhir.24
Keterangan mengenai Riwayat perawatan, perbaikan, dan modifikasi pressure vessel harus
dijelaskan dalam bentuk Berita Acara Pengambilan Keterangan kepada Pengurus tempat kerja.
Riwayat ini sangat berguna dalam mengetahui maintenance dan perubahan yang telah dilakukan
terhadap bejana tekanan. Pemenuhan syarat-syarat K3 yang menjadi catatan pada Laporan
pemeriksaan dan pengujian K3 sebelumnya harus dapat dipastikan bahwa telah dipenuhi secara
baik. Bila perlu dilengkapi dengan bukti fisik, dokumentasi hasil tindak lanjut cross check di
lapangan. Data umum dan Data Teknik yang disampaikan agar dapat selengkap mungkin,
sekurang-kurangnya sebagaimana data yang tercantum pada Formulir 2 Lampiran Permenaker No.
37 Tahun 2016.
Pemeriksaan pada bagian utama Pressure vessel, baru terbatas pada bagian shell/badan,
head/tutup ujung, dan jacket/selubung. Laporan mengenai pemeriksaan pada bagian pipa-pipa dan
Nozzle-nozzle masih belum dilakukan. Padahal potensi peledakan juga dapat terjadi pada
sambungan pipa-pipa dan las-lasan pada nozzle. Pemeriksaan persyaratan dan pengujian kelaikan
Safety devices (alat pengaman) Pressure vessel masih terbatas pada bagian manometer/pressure
gauge, strip merah pada tekanan tertinggi manometer, tingkap pengaman atau alat pengaman
sejenis, tanda pengenal pressure vessel. Safety devices Pressure vessel untuk bagian lainnya
seperti: Pengukur Temperatur, Keran Coba, Pipa Pembuang, Katup Penutup, Alat anti guling,
regulator penurun tekanan, pewarnaan pressure vessel, register bejana tekanan, dan Label belum
menjadi bagian dari kegiatan pemeriksaan dan pengujian. Alat Pengaman adalah alat perlengkapan
yang dipasang secara permanen pada bejana tekanan atau tangki timbun agar aman digunakan.
Tingkap Pengaman / Safety Valve berfungsi untuk mengeluarkan tekanan berlebih dari dalam
pressure vessel secara otomatis apabila tekanan di dalam pressure vessel telah melebihi tekanan
maksimum yang diizinkan. Manometer berfungsi untuk menunjukan tingginya tekanan di dalam
Pressure vessel. Flens Coba berfungsi untuk tempat dudukan manometer uji guna mengetahui
apakah tekanan yang ditunjukan oleh manometer dari pressure vessel masih sama dengan tekanan
yang ditunjukan pada manometer uji.25
Pemeriksaan persyaratan dan kelaikan pada bagian support pressure vessel hanya terbatas
pada pemeriksaan visual. Perhitungan teknis kekuatan pondasi, kekuatan pengait angkat, dan
pengujian corrosive pada pressure vessel sangat penting dilakukan terkait pertanggungjawaban
kelaikan secara ilmiah. Begitu juga untuk instalasi pipa yang terhubung pada bagian pressure
vessel. Penggunaan Air Receiver Tank pada Compressor seringkali dimodifikasi dengan instalasi
pipa dan bejana tambahan yang berfungsi sebagai penampung sementara dan selanjutnya menjadi
alat untuk membagikan media isi ke bagian-bagian yang dibutuhkan lainnya. Modifikasi instalasi
pipa dan bejana tambahan ini seringkali merupakan produk tambahan di luar produksi dari
pabrikan (dibuat sendiri atau melalui kontraktor lokal). Dengan Tekanan kerja yang sama dengan
Air Receiver Tank dari Compressor tentunya bagian instalasi pipa dan bejana tambahan ini menjadi
bagian yang krusial untuk potensi peledakan karena penggunaan pressure vessel. Penimbangan
berat untuk botol LPG, telah dilakukan dengan ketentuan tidak boleh lebih besar atau lebih kecil
5% (lima persen) dari berat semula. Pengukuran dimensi Pressure vessel, juga masih terbatas pada
bagian shell/badan dan head/tutup ujung, saja. Pengukuran dimensi pada bagian pipa-pipa dan
Nozzle-nozzle masih belum dilakukan.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 102
Catatan pada percobaan padat adalah tekanan uji yang belum sesuai dengan maksimum
allowable working pressure (MAWP). Berdasarkan Permenaker No. 37 Tahun 2016, tekanan uji
untuk percobaan padat sebesar 1,5 kali dari tekanan kerja. Perhitungan ulang kekuatan konstruksi
masih belum maksimal karena tidak dilakukannya pengujian tidak merusak secara lengkap
terutama untuk pengukuran ketebalan pelat dan pengukuran nilai kekerasan material secara actual
setelah beberapa watktu pemakaian. Selain itu, masih terdapat ketidaksesesuaian penggunaan
rumus/formula dari standar perhitungan yang digunakan. Kategori failures pada pressure vessels
antara lain: (1) Material – penggunaan material yang tidak tepat, cacat pada material, (2) Design –
data design yang tidak akurat, metode design yang tidak tepat, pemeriksaan design yang tidak
tepat, (3) Pabrikasi – Quality Control yang buruk, prosedur pembuatan yang tidak standar,
meliputi: pengelasan, heat treatment, metode pembentukan, (4) Pemeliharaan – pemakai, operator,
teknisi.26
KESIMPULAN DAN SARAN
Syarat-syarat pemeriksaan dan pengujian K3 pressure vessel yang sebagian telah
memenuhi Permenaker No. 37 Tahun 2016 antara lain: (1) Pemeriksaan gambar konstruksi /
instalasi, (2) Pemeriksaan sertifikat bahan dan keterangan lainnya, (3) Pemeriksaan Hasil penelitian
didapatkan syarat-syarat pemeriksaan dan pengujian K3 pressure vessel yang telah memenuhi
Permenaker No. 37 Tahun 2016 antara lain: (1) Pemeriksaan Data Umum, (2) Pemeriksaan Data
Teknik untuk bagian Shell / badan dan Head / tutup, (3) Pemeriksaan persyaratan dan kelaikan K3
untuk bagian Shell / badan, Head / tutup, dan Selubung / jacket (4) Pemeriksaan persyaratan dan
pengujian kelaikan safety devices: Manometer, Strip merah pada tekanan kerja tertinggi
manometer, Tingkap pengaman atau alat pengaman sejenis dan Tanda pengenal Bejana Tekanan
(nameplate / slug letter), (5) Pemeriksaan persyaratan dan kelaikan support, (6) Pemeriksaan
persyaratan dan kelaikan instalasi pipa, (7) Penimbangan berat (untuk pressure vessel dengan
volume sampai dengan 60 liter), (8) Pengukuran dimensi untuk bagian Shell / badan dan Head /
tutup, (9) SKP AK3 PUBT dari Kemenaker R.I. dan masih dalam masa berlaku, (10) SPK PJK3
bidang pemeriksaan dan pengujian teknik PUBT dari Kemenaker R.I. dan masih dalam masa
berlaku.lisensi K3 teknisi dan juru las, (4) Pemeriksaan persyaratan dan pengujian kelaikan safety
devices: Pengukur temperature dan alat anti guling, (5) Pengujian tidak merusak / Non Destructive
Test (NDT), untuk bagian Shell / badan dan Head / tutup, (6) Percobaan pemadatan (hydrostatic
test), (7) Perhitungan ulang kekuatan konstruksi (re-calculation).
Syarat-syarat pemeriksaan dan pengujian K3 pressure vessel yang belum memenuhi
Permenaker No. 37 Tahun 2016 antara lain: (1) Perhitungan kekuatan desain konstruksi (design
calculation); (2) Register pressure vessel; (3) Riwayat perawatan pressure vessel; (4) Riwayat
perbaikan (termasuk pergantian spare part) pressure vessel; (5) Riwayat modifikasi pressure
vessel; (6) Pemenuhan syarat-syarat K3 pada Laporan pemeriksaan dan pengujian K3 sebelumnya;
(7) Pemeriksaan data teknik untuk bagian pipa-pipa / channel dan Instalasi pipa; (8) Pemeriksaan
persyaratan dan kelaikan K3, untuk bagian Pipa-pipa / channel dan Nosel / nozzle; (9) Pemeriksaan
persyaratan dan pengujian kelaikan safety devices: keran coba, pipa pembuangan, katup penutup,
alat pembuang gas, pewarnaan, register pressure vessel, dan label; (9) Pengukuran dimensi untuk
bagian: pipa-pipa / channel, instalasi pipa, dan nosel / nozzle; (10) Pengujian tidak merusak / Non
Destructive Test (NDT), untuk bagian: pipa-pipa / channel, nosel / nozzle, dan Instalasi pipa.
Pembinaan, pengawasan, media dan proses evaluasi yang lebih ketat sangat dibutuhkan untuk
menjamin pelaksanaan riksa uji K3 pressure vessel telah memenuhi persyaratan sebagaimana
peraturan dan standar yang berlaku.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 103
DAFTAR PUSTAKA
1. Kementerian Ketenagakerjaan R.I., Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 37
Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun,
Jakarta. 2016.
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.,
Administrasi Teknis Pengawasan Bejana Tekanan. Modul Diklat Pengawas Spesialis
Pesawat Uap dan Bejana Tekan. Jakarta: 2014.
3. Widharto, Sri, Inspeksi Teknik Buku 2. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
4. ASME Boiler and Pressure vessel Committee on Pressure vessels, An International Code
VIII Rules for Construction of Pressure vessels Division 1. New York: The American
Society of Mechanical Engineers, 2015.
5. Djokosetyardjo, Ketel Uap. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006.
6. Shishesaz, Mohammad Reza, et. al. Comparison of API 510 pressure vessels inspection
planning with API 581 risk-based inspection planning approaches. Elsevier, International
Journal of Pressure Vessels and Piping 111-112 (2013) 202 - 208.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpvp.2013.07.007
7. Hadi, Syamsul, Teknologi Bahan. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016.
8. Schonmetz, Ing. Alois, dan Karl Gruber, Pengetahuan Bahan dalam Pengerjaan Logam.
Bandung: Penerbit Angkasa, 2013.
9. Ferdiana, Maria Dwi, Pengenalan Dasar dan Manajemen Material Baja. Yogyakarta: TAKA
Publisher, 2014.
10. Anrinal, Metalurgi Fisik. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013.
11. Djamaludin, Pengaruh Parameter Las terhadap Sifat Mekanik Sambungan Las pada
Pabrikasi Bejana Tekan untuk Industri Minyak dan Gas Bumi. Depok: Universitas Indonesia,
2015.
12. Sumaryanto, Ketel Uap Pipa Air Tinjauan dari Sisi Safety di Pabrik Pengolahan Kelapa
Sawit. Mojokerto: Sepilar Publishing House, 2017.
13. Widharto, Sri, Buku Pedoman Ahli Pemasang Pipa. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
14. Raswari, Teknologi dan Perencanaan Sistem Perpipaan. Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, 2010.
15. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.,
Korosi dan Pencegahannya. Modul Diklat Pengawas Spesialis Pesawat Uap dan Bejana
Tekan. Jakarta: 2014.
16. Prasetio, Agung Yudhi, Studi Kelayakan Operasi pada Jenis Bejana Tekan yang telah
mengalami Aging dengan Menggunakan Standar API 579/ASME FFS-1 dan Simulasi
Software PV-Elite. Depok: Universitas Indonesia, 2016.
17. Widharto, Sri, Inspeksi Teknik Buku 1. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
18. Daryanto, Teknik Las. Bandung: Alfabeta, 2013.
19. Abadi, Kurniawan, Prediksi Sisa Umur Bejana Tekan Absorber, Separator dan Filter pada
Fasilitas Pra-Pemrosesan Gas. Depok: Universitas Indonesia, 2016.
20. Satrijo, Djoeli dan Syarief Afif Habsya, Perancangan dan Analisa Tegangan pada Bejana
Tekan Horizontal dengan Metode Elemen Hingga. Rotasi Jurnal Teknik Mesin Undip – Vol.
14, No. 3, Juli 2012, p. 32 – 40.
21. Kementerian Tenaga Kerja R.I., Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor
PER.04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jakarta:
1995.
22. Widharto, Sri, Welding Inspection. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2013.
23. Sofyan, Bondan T., Pengantar Material Teknik. Jakarta: Salemba Teknika, 2010.
24. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I., Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi R.I. Nomor Per.02/MEN/1982 tentang Kwalifikasi Juru Las di Tempat Kerja,
Jakarta. 1982.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 104
25. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.,
Alat-Alat Pengamanan pada Bejana Tekanan. Modul Diklat Pengawas Spesialis Pesawat
Uap dan Bejana Tekan. Jakarta: 2014.
26. Moss, Dennis, Pressure Vessel Design Manual: Illustrated procedures for solving major
pressure design problems. Thrid Edition. UK: Elsevier, 2004.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 105
PERAN CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA PENCEGAHAN
KEMATIAN AKIBAT COVID-19 DI INDONESIA
Siti Masitoh
*, Teti Tejayanti, Sugiharti, Heny Lestary, Helena Ullyartha
Pangaribuan Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat, Badan Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan
Jl. Percetakan Negara no.29, Johar Baru, Jakarta Pusat
Corresponding email : [email protected]
THE ROLE OF COMPLETE BASIC IMMUNIZATION COVERAGE IN
PREVENTION OF CASE FATALITY RATE OF COVID-19 IN INDONESIA
ABSTRACT
COVID-19 cases continue to rise in Indonesia, hitting 200,000 cases with a fatality rate about 4 %, which is
higher than the global figure (3.2 %) and the second highest in Southeast Asia. The mortality rate for
COVID-19 varies across the provinces, therefore important to examine the causes of these differences.
Immunization is one of the most beneficial and cost-effective strategies to prevent disease. Vaccines activate
the body's own immune system to protect a person from subsequent infection or disease. The purpose of this
research is to determine how immunization contributes to Case fatality rate (CFR) of COVID-10 at sub-
national level. This cross-sectional study uses secondary data, including COVID-19 National data by
provincial, Basic Health Study 2018, SIRS online of Ministry of Health data, and The Central Bureau of
Statistics data. The unit analysis is the provincial level with a total sample of 170 samples. Cumulative cases
collected from April to August and analyze reviewed on a monthly basis. The dependent variable is CFR the
provincial level and the independent variable is the proportion of complete basic immunization and will be
regulated by population density, proportion of elderly people, poor behavior, environmental status (access to
water, sanitation and hygiene), nutritional status, non-communicable disease status and health service
facilities.The study was conducted using a 95% CI multivariate linear regression analysis. The findings
indicate that complete basic immunization is associated with a reduction in the mortality rate of COVID-19
at province leve. If the 10 per cent increase in immunization coverage is correlated with a 0.6 per cent
reduction in mortality or 6 deaths out of 1,000 confirmed positive cases. Understanding the effect of basic
immunization on the mortality rate of COVID-19, the national program needs to scale-up the fully-
immunized child campaign to achieve high immunization coverage as part of preventive action.
Keywords: CFR, complete basic immunization , COVID-19, risk faktor
ABSTRAK
Kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat bahkan mencapai lebih dari 200.000 kasus dengan tingkat
kematian sekitar 3,6% dimana angka ini lebih tinggi dari angka global (2,9%) dan menempati urutan kedua
kasus tertinggi di Asia Tenggara. Tingkat kematian COVID-19 antar provinsi beragam sehingga perlu dilihat
faktor apa yang menyebabkan perbedaan tersebut. Imunisasi adalah salah satu strategi yang paling
menguntungkan dan hemat biaya untuk mencegah penyakit. Imunisasi mengaktifkan sistem kekebalan tubuh
untuk melindungi seseorang dari infeksi atau penyakit berikutnya. Studi ini bertujuan untuk melihat peran
imunisasi terhadap kematian COVID-19 provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain cross
sectional menggunakan data sekunder yaitu data laporan kasus COVID-19 provinsi Kementerian Kesehatan,
Riset Kesehatan Dasar 2018, SIRS online imunisasi dasar lengkap, dan data BPS. Unit analisis yang
digunakan adalah provinsi dengan jumlah sampel 170 sampel. Kasus kumulatif dikumpulkan dari April
hingga Agustus dan ditinjau setiap bulan.Variabel dependen adalah case fatality rate provinsi, dan variabel
independen proporsi imunisasi dasar lengkap dan akan dikontrol dengan kepadatan penduduk, kemiskinan,
proporsi lansia, proporsi perilaku buruk, status lingkungan (air layak), status gizi, penyakit tidak menular dan
fasilitas pelayanan kesehatan. Analisis dilakukan menggunakan analisis multivariat regresi linear berganda
dengan 95% CI. Hasil menunjukkan bahwa imunisasi lengkap berasosiasi dengan penurunan angka kematian
COVID-19 di provinsi. Setiap kenaikan 10% cakupan proporsi imunisasi diasosiasikan dengan penurunan
angka kematian sebesar 0,6% atau 6 kematian dari 1000 kasus konfirmasi positif.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 106
Melihat pentingnya peran imunisasi lengkap terhadap angka kematian COVID-19, perlu program nasional
kampanye imunisasi lengkap pada anak untuk mencapai cakupan imunisasi yang tinggi sebagai tindakan
pencegahan.
Kata kunci : CFR, imunisasi dasar lengkap, COVID-19, faktor risiko
PENDAHULUAN
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi pandemi dunia sejak 11 Maret 2020.
Peningkatan jumlah kasus terjadi cukup cepat, dan menyebar ke berbagai negara dalam waktu
singkat termasuk Indonesia. Indonesia melaporkan kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020.
Kasus meningkat dan menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia menempati
urutan kedua negara di ASEAN dengan jumlah kasus konfirmasi terbanyak.1 Sampai dengan
tanggal 7 Oktober 2020 Gugus Tugas Percepatan COVID-19 melaporkan 315.714 kasus konfirmasi
COVID-19 dengan 11.472 kasus meninggal dan 240.291 kasus sembuh. Kematian akibat COVID-
19 di Indonesia termasuk tinggi (CFR 3,6%) bahkan melebihi angka kematian global (CFR 2,9%).1
Namun kasus COVID-19 baik jumlah kasus positif maupun angka kematian bervariasi antar
provinsi di Indonesia. Sebagai contoh provinsi dengan kasus terbanyak adalah DKI Jakarta
mencapai 82.190 kasus (26,0%), dan terendah Kepulauan Bangka Belitung 438 kasus (0,1%).2
Studi menyebutkan lokasi geografis dapat mempengaruhi variasi tingkat keparahan COVID-
19 karena dipengaruhi oleh usia individu dan faktor virus yang dimodifikasi oleh kepadatan
populasi, lingkungan, suhu udara sekitar, dan kelembapan. Selain variasi geografis yang
mempengaruhi penyebaran dan keparahan COVID-19, ada faktor lain seperti usia lanjut,
komorbiditas, dan faktor imunitas.3,4
Prevalensi dan angka kematian COVID-19 juga terlihat
berbeda antara negara-negara di Eropa Barat dan Eropa Timur. Ada banyak faktor geografis, sosial,
dan biologis seperti suhu, kelembaban, harapan hidup, pendapatan rata-rata, norma sosial, dan latar
belakang etnis, yang berpotensi dapat menjelaskan keragaman kasus COVID-19 antar negara.5
Indonesia dengan 34 provinsi tentu memiliki kondisi kesehatan masyarakat dan kondisi lingkungan
yang berbeda-beda. Status kesehatan masyarakat yang kurang baik akan lebih rentan terhadap
kasus penyakit menular. Oleh karena itu, perlu juga untuk menilai faktor-faktor yang berkontribusi
terhadap perbedaan kasus COVID-19 antar provinsi di Indonesia.
Salah satu program kesehatan yang mungkin berperan dalam meningkatkan imunitas suatu
kelompok masyarakat adalah imunisasi. Imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat paling
efektif dan efisien dalam mencegah beberapa penyakit berbahaya. Sejarah telah mencatat besarnya
peranan imunisasi dalam menyelamatkan masyarakat dunia dari kesakitan, kecacatan bahkan
kematian akibat penyakit-penyakit seperti Cacar, Polio, Tuberkulosis, Hepatitis B yang dapat
berakibat pada kanker hati, Difteri, Campak, Rubela dan Sindrom Kecacatan Bawaan Akibat
Rubela (Congenital Rubella Syndrom/CRS), Tetanus pada ibu hamil dan bayi baru lahir,
Pneumonia (radang paru), Meningitis (radang selaput otak), hingga Kanker Serviks yang
disebabkan oleh infeksi Human Papilloma Virus.6 Berbagai studi menyebutkan salah satu imunisasi
yang mungkin berkontribusi pada morbiditas dan mortalitas COVID-19 adalah imunisasi bacille
Calmette-Guérin (BCG). Negara dengan kebijakan vaksinasi universal BCG memiliki tingkat
kematian yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara yang tidak menerapkan BCG
pada anak-anak.7 Cakupan imunisasi antar provinsi di Indonesia juga bervariasi mulai dari yang
terendah Aceh (19,5%) sampai yang tertinggi bali (92,1%). Hal ini menjadi salah satu dasar
dilakukan studi ini untuk melihat peran imunisasi pada pencegahan kematian akibat COVID-19 di
Indonesia dengan membandingkan kondisi antar provinsi.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 107
METODE
Penelitian ini menggunakan desain cross sectional menggunakan data sekunder yaitu data
laporan kasus COVID-19 provinsi Kementerian Kesehatan, Riset Kesehatan Dasar 2018, SIRS
online Ditjen Yankes Kemenkes, dan data BPS. Studi ini merupakan bagian dari kajan ―Faktor-
faktor yang Berisiko terhadap Morbiditas dan Mortalitas Kasus COVID-19 di Wilayah Padat
Penduduk di Indonesia‖ yang telah mendapatkan persetujuan etik dari Komisi Etik Badan
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nomor LB.02.03/I/2767/2020.8
Unit analisis pada penelitian ini adalah provinsi dengan jumlah sampel 170. Jumlah sampel
menjadi lima kali lipat dari jumlah provinsi di Indonesia karena mengambil data kasus COVID-19
dari lima periode waktu yaitu April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020. Variabel dependen yang
kami pakai adalah case fatality rate yang dihitung dari kasus kematian COVID-19 dibagi dengan
kasus konfirmasi positif. Data kasus COVID-19 diperoleh dari data laporan kasus Kementerian
Kesehatan yang bisa didowload melalui website https://infeksiemerging.kemkes.go.id.1 Variabel
independen utama adalah proporsi cakupan imunisasi lengkap yang diperoleh dari data Riset
Kesehatan Dasar 20189 yang dikontrol oleh variabel lain yaitu kepadatan penduduk, kemiskinan,
proporsi lansia, , status lingkungan (air layak), status gizi, proporsi perilaku buruk, penyakit tidak
menular dan fasilitas pelayanan kesehatan. Variabel proporsi kemiskinan, dan status lingkungan
yang dilihat dengan proporsi air layak diperoleh dari BPS data dan informasi kemiskinan
kabupaten/kota 2019.10
Data Kepadatan penduduk dan proporsi lansia diperoleh dari data SUPAS
2015, dalam analisis kepadatan penduduk dibagi dalam 2 kategori yaitu padat penduduk jika di atas
nilai median dan tidak padat penduduk jika di bawah nilai median sedangkan data lansia dalam
bentuk proporsi. Provinsi juga dibedakan menjadi dua yaitu Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.
Variabel status gizi, perilaku buruk dan penyakit tidak menular diperoleh dari data Riset Kesehatan
Dasar 2018.9 Status gizi dilihat dari 4 variabel yaitu status gizi lebih pada balita, status gizi buruk
pada balita, status gizi lebih dan obesitas pada dewasa (umur>18 tahun) dalam bentuk proporsi.
Variabel perilaku buruk merupakan komposit dari empat indikator yaitu aktifitas fisik kurang,
merokok, tidak konsumsi buah dan sayur, dan tidak melakukan cuci tangan yang benar dimana
masing-masing indikator sudah dikategorikan menjadi 1 jika proporsi ≥ median, dan 0 jika proporsi
< median. Provinsi dikategorikan memiliki perilaku buruk jika ada satu atau lebih dari indikator
tersebut bernilai 1. Penyakit tidak menular dinilai dari empat variabel yaitu hipertensi, diabetes,
jantung dan kanker dalam bentuk proporsi. Fasilitas pelayanan kesehatan dinilai dari dua variabel
yaitu variabel ratio tempat tidur dan ratio ventilator yang diperoleh dari data Sistem Informasi
Rumah Sakit Online (SIRS Online). Data dibagi menjadi dua kategori yaitu mencukupi dan tidak
mencukupi.
Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap yaitu analisis univariat, bivariat dan
multivariat. Analisis univariat dilakukan untuk melihat deskripsi sampel, bivariat dilakukan dengan
uji T-test dan regresi linear untuk melihat korelasi dan analisis multivariat dilakukan dengan regresi
linear berganda dengan metode backward dengan tingkat kepercayaan 95%. Data dianalisis secara
kuantitatif menggunakan aplikasi statistik SPSS versi 20.
HASIL PENELITIAN
Rata-rata angka kematian akibat COVID-19 di provinsi di Indoensia adalah 4,32%. Artinya
ada 4 dari 100 orang yang terinfeksi COVID-19 yang meninggal. Namun, tingkat kematian di
provinsi cukup beragam ada yang belum ada sama sekali kematian dan kematian tertinggi 27,91%.
Rata-rata cakupan imunisasi dasar lengkap sudah lebih dari 50%, dan rata-rata proporsi kemiskinan
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 108
di provinsi sekitar 10%. Rata-rata proporsi lansi sekitar 7,54%, air layak 66,86%, BB lebih pada
dewasa 13,65%, obesitas 21,70%, gizi buruk pada balita 4,44%, gizi lebih pada balita 3,26%.
Untuk penyakit tidak menular hipertensi menempati urutan pertama dengan 31,07%, kemudian
penyakit jantung sebesar 14,38%, diabetes 13,76% dan kanker 1,75%. Tabel 3 menyajikan
gambaran karakteristik provinsi dari data kategorik. Kepadatan penduduk terbagi merata antara
yang padat penduduk dan yang tidak padat penduduk. Sebagian besar provinsi (88,2%) tergolong
memiliki perilaku masyarakat yang buruk. Jika dilihat dari indikator fasilitas pelayanan Kesehatan,
sebagian besar provinsi sudah memiliki kecukupan ventilator (81,8%) dan kecukupan ratio tempat
tidur (73,5%).
Tabel 1. Gambaran Karakteristik Provinsi
Variabel Mean Median Min-max
CFR 4,32% 3,82% 0 – 27,91% Imunisasi lengkap 56,18% 57,60% 19,5% - 92,1%
Kemiskinan 10,63% 8,76% 3,47% - 27,53%
Lansia 7,54% 7,25% 3,20% - 13,80%
Air layak 66,86% 63,34% 33,95% - 85,51% BB lebih pada dewasa 13,65% 13,35% 8,8% - 16,3%
Obesitas dewasa 21,70% 21,05% 10,3% - 30,2%
Gizi buruk pada balita 4,44% 4,45% 2,0% - 7,4%
Gizi lebih pada balita 3,26% 3% 1,1% - 7,4% Hipertensi 31.07% 29,83% 22,22% - 44,13%
Diabetes 13,76% 13,0% 6% - 26%
Jantung 14,38% 14,50% 7% - 22% kanker 1,76% 1,56% 0,85% - 4,86%
Tabel 2. Gambaran Karakteristik Provinsi (2)
Variabel n %
Kepadatan Penduduk
Padat 85 50%
Kurang padat 85 50%
Perilaku
Buruk 150 88,2
Baik 20 11,8 Ventilator
Kurang 31 18,2
Cukup 139 81,8
Ratio tempat tidur Kurang 45 26,5
Cukup 125 73,5
Total 170 100,0
Tabel 3 dan 4 menyajikan faktor-faktor yang berhubungan dengan angka kematian akibat
COVID-19 dengan analisis bivariat regresi liniear dan T-test. Variabel yang berhubungan dengan
angka kematian COVID-19 yaitu kemiskinan, proporsi lansia, obesitas pada dewasa, diabetes,
kepadatan penduduk, perilaku, dan ventilator.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 109
Tabel 3. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Angka Kematian Akibat COVID-19
(analisis regresi liniear)
Variabel R R2 Koef p-value
Imunisasi lengkap 0,054 0,003 -0,011 0,481 Kemiskinan 0,173 0,030 -0,104 0,024*
Lansia 0,185 0,034 0,273 0,016*
Air layak 0,048 0,002 -0,015 0,535
BB lebih pada dewasa 0,125 0,016 0,327 0,105 Obesitas dewasa 0,162 0,026 0,130 0,035*
Gizi buruk pada balita 0,136 0,019 -0,306 0,077
Gizi lebih pada balita 0,079 0,006 0,215 0,308
Hipertensi 0,084 0,007 0,060 0,278 Diabetes 0,196 0,038 0,134 0,010*
Jantung 0,091 0,008 0,089 0,238
kanker 0,063 0,004 0,311 0,412
Tabel 4. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Angka Kematian Akibat COVId-19
(analisis t-test)
Variabel n mean T-test p-value
Kepadatan Penduduk
- Padat penduduk 85 5,4278 4,507 0,001*
- Tidak padat 85 3,2148
Perilaku - Buruk 150 4,6149 5,150 0,001*
- Baik 20 2,1194
Ventilator
- Cukup 139 4,5853 -2,181 0,031* - Tidak cukup 31 3,1374
Rasio Tempat Tidur
- Cukup 125 4,3676 -0,297 0,767
- Tidak cukup 45 4,1928
Tabel 5. Model Akhir Analisis Multivariat Faktor yang Mempengaruhi Kematian
Akibat COVID-19 di Indonesia
Variabel Exp
(B)
95% CI t p-
value
Konstanta -0,314 -4,585 – 3,958 -0,145 0,885
Imunisasi lengkap -0,060 -0,091 - -0,028 -3,769 0,001
Kepadatan penduduk 2,536 1,419 – 3,652 4,483 0,001 Lansia 0,500 0,204 – 0,796 3,338 0,001
Perilaku 2,839 1,402 – 4,277 3,900 0,001 Air layak -0,094 -0,142 – -0,046 -3,847 0,001
Obesitas dewasa 0,198 0,059 – 0,336 2,820 0,005
Gizi lebih pada balita 0,509 0,055 – 0,963 2,216 0,028
Ratio tempat tidur 1,156 -0,081 – 2,394 1,845 0,067
Nilai Adjusted R2 = 30%
Model akhir analisis multivariat faktor yang mempengaruhi kematian akibat COVID-19 di
Indonesia disajikan pada table 5. Hasil menunjukkan bahwa imunisasi lengkap berasosiasi dengan
penurunan angka kematian COVID-19 di provinsi. Setiap kenaikan 10% cakupan proporsi
imunisasi diasosiasikan dengan penurunan angka kematian sebesar 0,6% atau 6 kematian dari 1000
kasus konfirmasi positif. Hasil ini sudah dikontrol oleh variabel lain yaitu kepadatan penduduk,
proporsi lansia, perilaku, proporsi air layak, proporsi obesitas pada dewasa, proporsi gizi lebih pada
balita dan ratio tempat tidur. Provinsi yang padat penduduk memiliki asosiasi terhadap peningkatan
angka kematian COVID-19 sebesar 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi yang tidak
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 110
padat penduduk. Setiap kenaikan 10% proporsi lansia dalam suatu provinsi diasosiasikan dengan
peningkatan angka kematian COVID-19 sebesar 5% atau 5 dari 100 kasus konfirmasi positif.
Provinsi yang tergolong perilaku masyarakatnya buruk (komposit dari tidak cuci tangan pakai
sabun, kurang aktivitas fisik, merokok dan tidak konsumsi buah dan sayur) memiliki risiko
peningkatan angka kematian akibat COVID-19 2,8 kali lebih tinggi dibandingkan provinsi yang
perilaku masyarakatnya baik. Setiap kenaikan 10% proporsi air layak di suatu provinsi
diasosiasikan dengan penurunan angka kematian akibat COVID-19 sebesar 0,94% atau 94
kematian dari 1000 kasus konfirmasi positif. Setiap kenaikan 10% kasus obesitas pada dewasa di
suatu provinsi diasosiasikan dengan peningkatan angka kematian akibat COVID-19 sebesar 1,98%
atau sekitar 2 kematian per 100 kasus konfirmasi positif. Setiap kenaikan 10% kasus gizi lebih pada
balita di suatu provinsi diasosiasikan dengan peningkatan angka kematian akibat COVID-19
sebesar 5,09% atau sekitar 5 kematian per 100 kasus konfirmasi positif dan provinsi yang
kekurangan tempat tidur memiliki risiko 1,15 kali lebih tinggi memiliki angka kematian COVID-
19.
PEMBAHASAN
Angka kematian COVID-19 dalam studi ini sebesar 4,32% jika dibandingkan dengan data
per 6 Oktober 2020 angka ini lebih tinggi dari angka kematian secara global (3,0%) dan angka
nasional (3,7%).11
Studi ini mengambil data kasus terakhir pada tanggal 28 Agustus 2020 artinya
sudah lebih dari sebulan dari data sekarang, dalam kurun waktu satu bulan kasus terus bertambah
dan jumlah pemeriksaan PCR juga terus ditingkatkan. Hal ini berpengaruh terhadap angka CFR/
angka kematian akibat COVID-19.
Studi ini memiliki beberapa keterbatasan. Data yang digunakan dalam studi ini merupakan
data sekunder dari Riset Kesehatan Dasar, data laporan kasus COVID-19, data BPS dan data SIRS
online dimana variabel yang ada menyesuaikan dengan ketersediaan data yang ada. Data yang
dianalisis berbeda waktu antara variabel dependen dengan independen. Variabel dependen
diperoleh tahun 2020 sedangkan variabel independen diperoleh tahun 2018 dan 2019. Data yang
diperoleh juga merupakan data crossectional sehingga tidak bisa memberikan gambaran sebab
akibat. Selain itu angka kematian akibat COVID-19 dengan CFR (case fatality rate) banyak
dipengaruhi oleh variabel fasilitas pelayanan kesehatan (facility based) namun karena keterbatasan
data, kami hanya memasukkan variabel ratio tempat tidur terhadap jumlah penduduk dan ratio
ventilator saja yang mungkin masih kurang untuk bisa menggambarkan kemampuan fasilitas
pelayanan kesehatan dalam menangani COVID-19. Namun penelitian ini juga memiliki kelebihan
karena penelitian yang berbasis komunitas dengan melihat status kesehatan secara komunitas masih
jarang dilakukan terutama yang berkaitan dengan COVID-19 sehingga studi ini bisa menjadi
masukan dan tambahan pengetahuan untuk COVID-19 terutama untuk kasus di Indonesia.
Hasil studi ini menunjukkan bahwa imunisasi lengkap berperan dalam menurunkan angka
kematian COVID-19 di provinsi. Setiap kenaikan cakupan proporsi imunisasi sebesar 10% dapat
menurunkan angka kematian sebesar 0,6% atau 6 kematian dari 1000 kasus konfirmasi positif
setelah dikontrol oleh variabel lain yaitu kepadatan penduduk, proporsi lansia, perilaku, proporsi
air layak, proporsi obesitas pada dewasa, proporsi gizi lebih pada balita dan ratio tempat tidur.
Berbagai studi menyebutkan, salah satu vaksin yang dianggap berpengaruh terhadap morbiditas
dan mortalitas COVID-19 adalah vaksin bacille Calmette-Guérin (BCG). Vaksin BCG adalah
strain hidup yang dilemahkan yang berasal dari isolat Mycobacterium bovis yang digunakan secara
luas di seluruh dunia sebagai vaksin untuk Tuberkulosis (TB), dengan banyak negara, termasuk
Jepang dan Cina yang memiliki kebijakan vaksinasi BCG universal pada bayi baru lahir. Negara
lain seperti Spanyol, Prancis, dan Swiss, telah menghentikan kebijakan vaksin universal mereka
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 111
karena risiko yang relatif rendah penyakit TB sedangkan negara-negara seperti Amerika Serikat,
Italia, dan Belanda, belum mengadopsi kebijakan vaksin universal karena alasan serupa.12
Vaksin
BCG di Indonesia termasuk dalam vaksin dasar wajib bagi bayi baru lahir sejak tahun 1999, akibat
tingginya risiko TBC.
Virus coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus dengan struktur RNA sense positif beruntai
tunggal, dan vaksin BCG telah terbukti mengurangi keparahan infeksi oleh virus lain dengan
struktur yang sama dalam uji coba terkontrol.7 Vaksin BCG dapat memicu perubahan metabolik
dan epigenetik yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh secara luas untuk melawan
infeksi dengan cara memicu suatu bentuk memori kekebalan ―non-spesifik‖, yang disebut
kekebalan terlatih. Kekebalan terlatih dapat digunakan sebagai senjata jika terjadi infeksi
berikutnya.7,3
BCG memiliki efek menguntungkan pada kekebalan terhadap berbagai infeksi terkait
paru-paru seperti tuberkulosis dan berbagai infeksi saluran pernapasan terutama akibat pneumonia
dan sepsis.13,3,7,14,15
Namun, kemungkinan efek perlindungan BCG mungkin tidak secara langsung
terkait dengan tindakan pada COVID-19 tetapi pada infeksi atau sepsis yang terjadi bersamaan.
Selain itu, ditemukan bahwa vaksinasi BCG berkorelasi dengan penurunan jumlah infeksi COVID-
19 yang dilaporkan di suatu negara yang menunjukkan bahwa BCG mungkin memberikan
perlindungan khusus terhadap COVID-19.12
Oleh karena itu, sementara vaksin khusus virus
COVID-19 sedang dikembangkan, terdapat cukup data untuk mendukung evaluasi vaksinasi BCG
sebagai cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan menjadikan vaksin BCG sebagai kandidat
yang menjanjikan untuk melawan COVID-19.15
Hasil studi ini sejalan dengan hasil studi awal sebelumnya dengan unit analisis negara bahwa
negara dengan kebijakan universal vaksinasi BCG memiliki tingkat kematian yang jauh lebih
rendah jika dibandingkan dengan negara yang tidak menerapkan BCG pada anak-anak.7 Vaksinasi
BCG tampaknya mengurangi kematian secara signifikan terkait COVID-19. Semakin awal suatu
negara menetapkan kebijakan vaksinasi BCG, semakin kuat pengurangan jumlah kematian per juta
penduduk, konsisten dengan gagasan bahwa melindungi populasi lansia mungkin penting dalam
mengurangi kematian.12
Secara khusus, tingkat pertumbuhan kasus COVID-19 jauh lebih lambat di
negara-negara dengan vaksinasi BCG yang diwajibkan, dibandingkan dengan negara-negara tanpa
vaksinasi BCG.13
Seperti kasus di Jepang dan negara lain termasuk Cina, Korea, India, dan Rusia
yang memiliki vaksin BCG wajib untuk anak untuk melawan tuberkulosis. Negara-negara ini
sejauh ini memiliki tingkat kematian per kapita yang relatif rendah dari COVID-19 dibandingkan
dengan negara-negara yang tidak memiliki vaksin BCG wajib (AS, Spanyol, Prancis, Italia,
Belanda). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cakupan vaksin BCG pada anak muda
menunjukkan efek perlindungan terhadap penyebaran COVID-19 lokal di Jepang. Namun,
kemungkinan relevansi vaksinasi BCG bayi dengan mortalitas tinggi di antara pasien lansia dengan
COVID-19 masih perlu diteliti.16
Variabel lain sebagai variabel kontrol yang berperan terhadap angka kematian akibat
COVID-19 adalah faktor perilaku. Pada studi ini perilaku merupakan komposit dari empat variabel
yaitu tidak mencuci tangan dengan sabun, tidak melakukan aktifitas fisik, merokok dan tidak
mengonsumsi buah dan sayur. Perilaku dikatakan buruk jika ada ada salah satu atau lebih dari
komponen perilaku tersebut bernilai buruk karena satu sama lain dari komponen perilaku tersebut
saling berkaitan. Sering mencuci tangan dengan sabun selama setidaknya 20 detik sangat
disarankan sebagai salah satu langkah preventif terhadap COVID-19. Hasil analisis regresi data
kebiasaan mencuci tangan dari 63 negara menunjukkan terdapat korelasi yang kuat antara budaya
mencuci tangan dan besarnya wabah di berbagai negara. Secara spesifik, negara yang
masyarakatnya tidak memiliki kebiasaan mencuci tangan cenderung memiliki eksposur yang jauh
lebih tinggi terhadap COVID-19.17
Aktifitas fisik juga penting untuk dilihat karena aktifitas fisik
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 112
dapat menurunkan stress sehingga dapat menjaga kesehatan mental yang secara tidak langsung juga
dapat meningkatkan kekebalan tubuh.18
Perilaku merokok juga penting untuk dimasukkan dalam
komponen perilaku. Sebuah studi sistematik review menyebutkan merokok dapat meningkatkan
tingkat keparahan COVID-19. Di antara pasien COVID-19 yang masih merokok memiliki risiko
keparahan 1,8 kali lebih tinggi dibandingkan yang tidak merokok, dan pasien yang memiliki
riwayat merokok sebelumnya memiliki risiko keparahan 1,31 kali lebih tinggi. 19
Selain itu, untuk
meningkatkan imunitas sebagai senjata untuk melawan infeksi kita juga perlu memperhatikan
konsumsi makanan. Oleh karena itu perilaku tidak mengonsumsi buah dan sayur juga kami
masukkan dalam komponen perilaku. Untuk membangun sistem imun diperlukan vitamin dan
minera. Sebagian besar vitamin dan seluruh mineral tidak dapat disintesa oleh tubuh sehingga harus
diperoleh dari makanan terutama buah, sayur dan pangan hewani. Untuk memenuhi kebutuhan
vitamin dan mineral ini maka diperlukan konsumsi makanan yang seimbang dan beragam.18
Dalam analisis ini ketersediaan air layak juga berperan terhadap angka kematian akibat
COVID-19. Setiap kenaikan 10% proporsi air layak di suatu provinsi akan menurunkan angka
kematian akibat COVID-19 sebesar 0,94% atau 94 kematian dari 1000 kasus konfirmasi positif.
Penyediaan air bersih, sanitasi, dan kondisi higienis sangat penting untuk melindungi kesehatan
masyarakat dari semua wabah penyakit menular, termasuk wabah COVID-19. Memastikan praktik
WASH (Water, Sanitation, and Hygiene) dan pengelolaan limbah yang baik dan diterapkan secara
konsisten di komunitas, rumah, sekolah, pasar, dan fasilitas pelayanan kesehatan akan semakin
membantu mencegah penularan virus COVID-19 dari manusia ke manusia.20
Selama pandemic seperti saat ini, kekurangan air bersih untuk minum dan sarana higienis
yang layak telah menjadi perhatian dunia. Negara – negara di Afrika dan Asia Selatan, dengan
sekitar 85% penduduk dunia, menghadapi tantangan yang menakutkan untuk mengakses air bersih,
terutama untuk daerah daerah kumuh, pinggiran kota, dan kamp pengungsian. Negara maju seperti
Amerika dan Eropa juga mengalami krisis air, sehingga banyak rumah tangga di sana memilih
membeli air kemasan sebagai kebutuhan air minumnya. Bahkan di negara terkaya di dunia, AS,
setidaknya masih ada sekitar dua juta orang yang tidak memiliki akses ke air ledeng 21
. Kebutuhan
air bersih sebelum dan setelah pandemi pasti berbeda. Pandemi menjadikan masyarakat lebih
memperhatikan kebersihan sehingga sering mencuci tangan dengan sabun sebagai salah satu upaya
untuk menekan penularan COVID-19. Oleh karena itu, peran ketersediaan air bersih menjadi salah
satu yang penting untuk diperhatikan dalam masa pandemi ini.
Status gizi juga berpengaruh terhadap kematian akibat COVID-19 terutama obesitas pada
dewasa dan gizi lebih pada balita. Setiap kenaikan 10% kasus obesitas pada dewasa di suatu
provinsi dapat meningkatkan angka kematian akibat COVID-19 sebesar 1,98% atau sekitar 2
kematian per 100 kasus konfirmasi positif. Setiap kenaikan 10% kasus gizi lebih pada balita di
suatu provinsi dapat meningkatkan angka kematian akibat COVID-19 sebesar 5,09% atau sekitar 5
kematian per 100 kasus konfirmasi positif. Obesitas berhubungan dengan respon imunitas yang
buruk dan akan berpengaruh pada pasien yang menderita penyakit pernapasan.22
Studi sebelumnya
menunjukkan bahwa kenaikan berat badan yang berlebihan ≥18 kg dapat meningkatkan risiko
mengalami pneumonia.23,24
Obesitas juga dapat mengganggu fungsi paru-paru. Pasien dengan
obesitas menggunakan oksigen dengan persentase yang lebih banyak untuk bernafas, yang
berakibat pada pengurangan kapasitas residu fungsional dan volume ekspirasi.25,26
. Kelainan
ventilasi-perfusi berikutnya dapat menurunkan cadangan ventilasi dan menyebabkan gagal
pernapasan.27,28
Selain itu, sub-analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa laki-laki dengan IMT ≥28
memiliki peluang peningkatan keparahan menjadi 4,4 kali lipat lebih tinggi, dengan hampir
setengah dari pasien laki-laki obesitas mengalami pneumonia berat. 22
. Penelitian lain menemukan
pasien dengan obesitas berat (IMT> 40 memiliki OR 2,8 dengan 95% CI 1,4-5,9 ) sedangkan IMT>
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 113
45 (OR, 4,2; 95% CI, 1,9-9,4) berisiko lebih tinggi untuk mengalami komplikasi dan kematian
akibat COVID-19.29
Jumlah kasus COVID-19 terus meningkat bahkan bisa mencapai 2000 kasus per hari akhir-
akhir ini. Lonjakan ini membuat daya tampung rumah sakit rujukan semakin tidak ideal seperti
contohnya di Jakarta dimana tempat tidur ruang isolasi yang terpakai sudah mencapai 69 persen
dan ruang perawatan intensif atau ICU 77 persen. Bila mengacu data Organisasi Kesehatan Dunia
atau WHO, maksimal keterpakaian tempat tidur di RS hanya 60 persen artinya seperti kasus di
Jakarta saja sudah melebihi kapasitas yang seharusnya.30
Hal ini tentu saja akan mempengaruhi
angka kematian COVID-19. Hasil penelitian ini menunjukkan kekurangan tempat tidur memiliki
risiko 1,15 kali lebih tinggi terhadap angka kematian COVID-19.
KESIMPULAN DAN SARAN
Imunisasi Dasar Lengkap memiliki asosiasi terhadap penurunan angka kematian
akibat COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan cakupan imunisasi
lengkap sebagai salah satu upaya menekan angka kematian COVID-19 atau memberikan
imunisasi tambahan untuk populasi berisiko seperti balita dan lansia.
DAFTAR PUSTAKA
1. Kementerian Kesehatan. Situasi Penyakit Infeksi Emerging [Internet]. 2020. Available from:
https://infeksiemerging.kemkes.go.id/downloads/?dl_cat=5#.X3fp5WgzY2w
2. Gugus Tugas Percepatan COVID-19. Data COVID-19 Per 7 Oktober 2020 [Internet].
www.covid19.go.id. 2020. Available from: https://covid19.go.id/peta-sebaran
3. Raghab Mohapatra P, Mishra B, Behera B. BCG vaccination induced protection from COVID-
19. Indian J Tuberc [Internet]. 2020;9438884288(xxxx):8–13. Available from:
https://doi.org/10.1016/j.ijtb.2020.08.004
4. Kang SJ, Jung SI. Age-Related Morbidity and Mortality among Patients with COVID-19.
Infect Chemother. 2020;52(2):154–64.
5. Sala G, Miyakawa T. Association of BCG vaccination policy with prevalence and mortality of
COVID-19. medRxiv [Internet]. 2020;2020.03.30.20048165. Available from:
https://doi.org/10.1101/2020.03.30.20048165%0Ahttp://medrxiv.org/lookup/doi/10.1101/2020
.03.30.20048165
6. Kementerian Kesehatan. Petunjuk Teknis Pelayanan Imunisasi pada Masa Pandemi COVID-
19. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2020.
7. Curtis N, Sparrow A, Ghebreyesus TA, Netea MG. Considering BCG vaccination to reduce
the impact of COVID-19. Lancet [Internet]. 2020;395(10236):1545–6. Available from:
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31025-4
8. Tejayanti T. Laporan Kajian Faktor-faktor yang Berisiko terhadap Morbiditas dan Mortalitas
Kasus COVID-19 di Wilayah Padat Penduduk di Indonesia (unpublished). Jakarta; 2020.
9. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas) Indonesia tahun 2018. Riset Kesehatan Dasar 2018. Jakarta: Lembaga Penerbit
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; 2018. p. 182–3.
10. Badan Pusat Statistik. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2019 [Internet].
Jakarta: CV. Nario Sari; 2019. Available from: https://www.m-
culture.go.th/mculture_th/download/king9/Glossary_about_HM_King_Bhumibol_Adulyadej‘s
_Funeral.pdf
11. Kementerian Kesehatan. Situasi Terkini Perkembangan Novel Coronavirus (COVID-19)
[Internet]. Kementerian Kesehatan. Jakarta; 2020. Available from:
https://covid19.kemkes.go.id/download/Situasi_Terkini_050520.pdf
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 114
12. Miller A, Reandelar MJ, Fasciglione K, Roumenova V, Li Y, Otazu GH. Correlation between
universal BCG vaccination policy and reduced morbidity and mortality for COVID-19: an
epidemiological study. J Chem Inf Model. 2019;53(9):1689–99.
13. Berg MK, Yu Q, Salvador CE, Melani I, Kitayama S. Mandated Bacillus Calmette-Guérin
(BCG) vaccination predicts flattened curves for the spread of COVID-19. J Chem Inf Model.
2019;53(9):1689–99.
14. Komine-Aizawa S, Yamazaki T, Yamazaki T, Hattori SI, Miyamoto Y, Yamamoto N, et al.
Influence of advanced age on Mycobacterium bovis BCG vaccination in guinea pigs
aerogenically infected with Mycobacterium tuberculosis. Clin Vaccine Immunol.
2010;17(10):1500–6.
15. Hegarty PK, Kamat AM, Zafirakis H, Dinardo A. BCG vaccination may be protective against
Covid-19. ResearchGate [Internet]. 2020;(March). Available from:
https://www.researchgate.net/publication/340224580 BCG
16. Kinoshita M, Tanaka M. Impact of routine infant BCG vaccination in young generation on
prevention of local COVID-19 spread in Japan: BCG vaccination prevent COVID-19 spread. J
Infect. 2020;(xxxx).
17. Pogrebna G, Kharlamov AA. The Impact of Cross-Cultural Differences in Handwashing
Patterns on the COVID-19 Outbreak Magnitude. Res Gate [Internet]. 2020;(March):10.
Available from: https://www.researchgate.net/publication/340050986%0AThe
18. Siswanto, Budisetyawati, Ernawati F. Peran Beberapa Zat Gizi Mikro Dalam Sistem Imunitas.
Gizi Indones. 2014;36(1):57–64.
19. Reddy RK, Charles WN, Sklavounos A, Dutt A, Seed PT, Khajuria A. The effect of smoking
on COVID-19 severity: A systematic review and meta-analysis. J Med Virol. 2020;
20. World Health Organization (WHO), (UNICEF) UNCF. Water, sanitation, hygiene and waste
management for the COVID-19 virus. World Heal Organ. 2020;1(March):1–9.
21. Tortajada C, Biswas AK. COVID-19 heightens water problems around the world. Water Int.
2020;45(5):441–2.
22. Qingxian C, Fengjuan C, Fang L, Xiaohui L, Tao W, Qikai W, et al. Obesity and COVID-19
Severity in a Designated Hospital in Shenzhen, China. SSRN Electron J.
2020;(202002073000001).
23. Morgan OW, Bramley A, Fowlkes A, Freedman DS, Taylor TH, Gargiullo P, et al. Morbid
obesity as a risk factor for hospitalization and death due to 2009 pandemic influenza A(H1N1)
disease. PLoS One. 2010;5(3):1–6.
24. Louie JK, Acosta M, Samuel MC, Schechter R, Vugia DJ, Harriman K, et al. A novel risk
factor for a novel virus: Obesity and 2009 pandemic influenza a (H1N1). Clin Infect Dis.
2011;52(3):301–12.
25. Baik I, Curhan GC, Rimm EB, Bendich A, Willett WC, Fawzi WW. A prospective study of
age and lifestyle factors in relation to community-acquired pneumonia in US men and women.
Arch Intern Med. 2000;160(20):3082–8.
26. Peters U, Dixon AE. The effect of obesity on lung function Ubong. Expert Rev Respir MEd.
2018;12(9):755–67.
27. Bahammam AS, Al-Jawder SE. Managing acute respiratory decompensation in the morbidly
obese. Respirology. 2012;17(5):759–71.
28. Zammit C, Liddicoat H, Moonsie I, Makker H. Obesity and respiratory diseases. Am J Clin
Hypn. 2011;53(4):335–43.
29. Louie JK, Acosta M, Samuel MC, Schechter R, Vugia DJ, Harriman K, et al. A novel risk
factor for a novel virus: Obesity and 2009 pandemic influenza a (H1N1). Clin Infect Dis.
2011;52(3):301–12.
30. Triyasni. INFOGRAFIS: Kapasitas Rumah Sakit COVID-19 Jakarta Hampir Penuh. Liputan 6
[Internet]. 2020; Available from: https://www.liputan6.com/news/read/4345460/infografis-
kapasitas-rumah-sakit-covid-19-jakarta-hampir-penuh
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 115
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAPADA PROSES PEMOTONGAN
BATU PADAS DI WORKSHOP SARI YASA KOTA DENPASAR
I Gusti Agung Haryawan¹
*, Komang Angga Prihastini², Ni Putu Diana Swandewi³
¹˒²Dosen Program Studi K3 Universitas Bali Internasional
³Mahasiswa Program Studi K3 Universitas Bali internasional
Jl. Seroja Gang Jeruk No. 9 Kelurahan Tonja Denpasar Bali 80239
Coresponding Email : [email protected]
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH IN THE PROCESS OF CUTTING PADAS
STONES AT THE SARI YASA WORKSHOP DENPASAR CITY
ABSTRACT
The rapid development of housing and building has recently had an impact on the workforce working in this
sector. Workers are required to have skills in accordance with their fields, including workers supplying stone
padas. When working in a standing position, the worker is always in wet condition due to the splashes used
to reduce dust when the rock is cut. These working conditions cause discomfort, fatigue, musculoskeletal
disorders and increased workload due to unnatural or ergonomic work environments and non-physiological
work attitudes.Therefore, it is necessary to do ergonomic-oriented work methods so that workers can work
productively in a comfortable, safe, healthy and efficient way. This research is experimental research by
using the same subject design (treatment by subject design) which is done in Workshop Sari Karya Denpasar
City. Three samples with multiple repetitions, the results showed a significant difference (p <0.05). In the
mean before the average treatment of stone stone cutting heart rate 63,666 ± 1,89 dpm, mean and
musculoskeletal complaint 32,466 ± 0,915, mean of fatigue 82,200 ± 1,897 and productivity average 458,333
± 14,840. After the average treatment of rock hard rock cutting rate 64,046 ± 2,12 dpm, mean of
musculoskeletal complaint 57,800 ± 5,634, mean of fatigue 66,266 ± 0,961. The ergonomic-oriented method
occupational safety and health decreased workload by 3.347%, musculoskeletal complaints by 25.33%,
fatigue 15.934%. shows that ergonomically oriented work methods occupational safety and health can
reduce workload, musculoskeletal complaints, fatigue.
Keywords: K3, working methods, stone cutters padas
ABSTRAK
Pesatnya pembangunan perumahan dan gedung belakangan ini yang berimbas pada tenaga kerja yang bekerja
di sektor konstruksi. Pekerja dituntut memiliki keterampilan sesuai dengan bidangnya, termasuk pekerja
pengadaan bahan batu padas. Pada saat bekerja dengan sikap berdiri, pekerja selalu dalam kondisi basah
akibat percikan air yang digunakan untuk mengurangi debu saat batu padas dipotong. Kondisi kerja ini
menimbulkan ketidaknyamanan, kelelahan, gangguan muskuloskeletal dan beban kerja yang semakin
meningkat karena lingkungan kerja yang tidak alami atau tidak ergonomis serta sikap kerja yang tidak
fisiologis. Untuk itu perlu dilakukan metode kerja yang mengacu pada keselamatan dan kesehatan kerja
sehingga pekerja dapat bekerja produktif dengan aman, nyaman, sehat dan efisien. Penelitian ini adalah
penelitian eksperimental dengan menggunakan rancangan sama subjek (treatment by subject design) yang
dilakukan di Workshop Sari Karya Kota Denpasar. Dari tiga sampel, hasil penelitian menunjukkan adanya
perbedaan bermakna (p<0,05). Pada sebelum perlakuan rerata denyut nadi kerja pemotong batu padas 63,666
± 1,89 dpm, rerata dan keluhan muskuloskeletal 32,466 ± 0,915, rerata kelelahan 82,200 ± 1,897. Sesudah
perlakuan rerata denyut nadi kerja pemotong batu padas 64.046 ± 2,12 dpm, rerata keluhan muskuloskeletal
57,800 ± 5,634, rerata kelelahan
66,266 ± 0,961. Metode berorientasi keselamatan dan kesehatan kerja menurunkan beban kerja sebesar
3,347%, keluhan muskuloskeletal sebesar 25,33%, kelelahan 15,934%. Menunjukkan bahwa metode kerja
berorientasi keselamatan dan kesehatan kerja dapat menurunkan beban kerja, keluhan muskuloskeletal dan
kelelahan.
Kata Kunci: K3, metode kerja , pemotong batu padas
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 116
PENDAHULUAN
Perkembangan pembangunan perumahan dan gedung perkantoran membawa tren bentuk dan
gaya dari desain bangunan. Penggunaan material dalam rancangan bangunan berpengaruh terhadap
hasil desain seorang desainer atau arsitek serta selera dari pemilik bangunan tersebut. Material-
material yang digunakan saat ini memang beragam jenis dan bentuknya, seperti: batu andesit, batu
basal, batu candi, batu padas, batu granit, batu palimanan dan batu paras jogya. Material-material
ini berasal dari berbagai daerah kota di Indonesia serta karakternya pun berbeda-beda. Penggunaan
material batu ini sebelum di aplikasikan ke bangunan atau yang lainnya melalui proses pemotongan
untuk mendapat ukuran yang standar.¹
Saat melakukan pekerjaan memotong batu padas, para pekerja mengambil posisi berdiri
menghadap mesin potong, kedua tangan memegang batu padas dengan ukuran 40x20x15 cm
dengan berat ± 5 kg. Batu padas akan didorong mendekati mesin potong dengan mata pisau yang
besar. Kondisi pekerja selama melakukan pekerjaannya dengan kondisi basah karena mesin potong
ini dilengkapi dengan slang air yang membasahi batu padas tersebut, dengan maksud meredam
debu yang dikeluarkan saat pemotongan batu padas tersebut. Pekerja hanya memakai pelindung
plastik untuk bagian tubuh di bawah pinggang dan tanpa alas kaki. Tingkat kebisingannya yang
ditimbulkan dari mesin potong ini 96 dBA selama 8 jam kerja sehingga sangat mengganggu
pendengaran. Ketidaknyamanan itu disebabkan oleh tingkat kelelahan, keluhan muskuloskeletal,
beban kerja.
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, menunjukkan pekerja bekerja dengan sikap kerja
yang tidak fisiologis yang meliputi bekerja berdiri dengan tidak memakai alas kaki, tidak memakai
afron atau pelindung badan secara keseluruhan serta kondisi lingkungan yang menimbulkan
kebisingan akibat dari suara mesin potong batu padas, sehingga mengakibatkan pekerja merasa ada
gangguan pendengaran, jari-jari tangan dan kaki lembab serta tubuh merasa kedinginan.
Hasil studi pendahuluan pada keluhan muskuloskeletal terhadap pekerja pemotong batu
padas, mengalami keluhan pada bahu kiri dan kanan (73%), pada lengan atas kiri dan kanan
(75%), pada betis kiri dan kanan (60%) dan pada tangan (75%). Untuk rerata denyut nadi kerjanya
adalah 103,42 ± 5,58 denyut permenit, dan hal ini termasuk beban kerja sedang.² Bekerja dengan
sikap berdiri dalam waktu relatif lama dengan kondisi kerja dengan tingkat kebisingan dan dingin/
lembab akan cepat menimbulkan rasa lelah. Posisi tubuh yang salah atau tidak fisiologis apalagi di
dalam sikap paksa jelas mengurangi produktivitas seseorang.³
Tuntutan tugas, kondisi lingkungan, dan organisasi kerja yang kurang proposional dapat
menimbulkan gangguan kesehatan, kelelahan, penurunan kewaspadaan, peningkatan angka
kecelakaan kerja dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan efesiensi dan produktivitas
kerja.4 Penelitian ini diharapkan mampu memperbaiki stasiun kerja yang mengacu pada konsep
ergonomi dan K3 yang meliputi pertimbangan teknis, kesehatan, keamanan, efektivitas dan
efisiensi. Sehingga dapat mengurangi kelelahan, keluhan muskuloskeletal, beban kerja.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental, dengan menggunakan rancangan sama
subjek (treatment by subject design).5 Rancangan sama subjek adalah rancangan serial, dimana
semua sampel mengalami perlakuan 1 dan juga perlakuan 2 dalam periode waktu yang berbeda.
Perlakuan 1 bekerja dengan keadaan seperti adanya, perlakuan 2 bekerja dengan intervensi
penggunaan afron seluruh tubuh, penggunaan sepatu boat dan menutup mesin pemotong batu
padas. Rancangan ini, selang antara periode waktu diperlukan washing out, untuk menghilangkan
efek perlakuan pertama terhadap perlakuan berikutnya.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 117
HASIL PENELITIAN
Tempat penelitian ini di Workshop Sari Karya yang berlokasi di daerah Denpasar dengan
sampel sebanyak 3 orang yang dalam pengambilan data diulang sebanyak 5 kali karena
keterbatasan pekerja dan stasiun kerja.
Tabel 1. Deskripsi Karakteristik Subjek Penelitian (n=3)
Variabel Rerata SB
Umur (th) 46,00 3,00
Berat badan (kg) 70,00 2,00
Tinggi badan (cm) 171,66 3,51
Berdasarkan tabel di atas rerata umur pemotong batu padas pada saat penelitian dilakukan
adalah 46,00 ± 3,00 tahun, dengan rerata berat badan 70,00 ± 2,00 kg, rerata tinggi badan 171,66 ±
3,51 cm. Dari umur, berat badan dan tinggi badan termasuk dalam kategori normal sedangkan
pengalaman kerja subjek termasuk dalam kategori berpengalaman atau cukup lama bekerja.
Tabel 2. Uji Perbedaan Skor Denyut Nadi (n=3)
Variabel Periode I Periode II Nilai
T Nilai
P n Rerata SB Rerata SB
Denyut nadi istirahat 3 63,66 1,89 64,04 2,12 -0,804 0,421 Denyut nadi kerja 3 123,87 3,01 115,37 2,68 -3,408 0,001
Nadi kerja 3 56,49 0,63 53,14 1,90 -3,409 0,001
Berdasarkan tabel di atas rerata denyut nadi kerja subjek pada sebelum perlakuan adalah
63,666 ± 1,89 dpm termasuk kategori beban kerja sedang. Rerata denyut nadi kerja subjek
penelitian pada sesudah perlakuan adalah 64,046 ± 2,12 dpm yang termasuk ke dalam kategori
kerja sedang. Nadi kerja pada stasiun kerja sebelum perlakuan reratanya 56,493 ± 0,632 dpm dan
pada stasiun kerja sesudah perlakuan 53,146 ± 1,908 dpm. Sehingga terjadi penurunan beban kerja
sebesar 3,347%.
Tabel 3. Uji Perbedaan Efek Sebelum dan Sesudah Perlakuan Beda Skor
Kelelahan (n=3)
Variabel Periode I Periode II
Nilai
T
Nilai
P Rerata SB Rerata SB
Kelelahan sebelum bekerja 41,26 0,96 41,06 0,703 -0,500 0,617 Kelelahan sesudah bekerja 82,20 1,89 66,26 0,96 -3,419 0,001
Selisih 40,93 2,34 25,20 1,47 17,753 0,000
Berdasarkan table di atas rerata skor kelelahan sebelum perlakuan adalah 41,266 ± 0,961
sebelum bekerja dan 41,066 ± 0,703 sesudah bekerja. Pada uji t-paired sesudah perlakuan
didapatkan skor kelelahan dengan rerata 82,200 ± 1,897 sebelum bekerja dan 66,266 ± 0,961
sesudah bekerja. Data rerata beda skor kelelahan sebelum perlakuan adalah 40,933 ± 2,344 dan
25,200 ± 1,473 setelah perlakuan. Hasil uji efek perbedaan skor sebelum dan sesudah kerja
sebelum perlakuan dengan sebelum kerja dan sesudah kerja sesudah perlakuan menggunakan uji
Wilcoxon menunjukkan p = 0,005 yang artinya berbeda secara signifikan antara sebelum dan
sesudah perlakuan. Sehingga terjadi penurunan kelelahan sebesar 15,934%.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 118
Tabel 4. Uji Perbedaan Efek Sebelum dan Sesudah Perlakuan Beda Skor Keluhan
Muskuloskeletal (n=3)
Variabel Periode I Periode II
Nilai
T Nilai P Rerata SB Rerata SB
Kelelahan sebelum bekerja 34,07 0,961 32,46 0,915 -3,448 0,001
Kelelahan sesudah bekerja 76,33 2,468 57,800 5,634 -3,424 0,001 Selisih 42,266 3,034 25,333 6,043 -3,415 0,001
Berdasarkan table di atas perbedaan rerata keluhan muskuloskeletal pada sikap kerja
sebelum perlakuan sebesar 34,066 ± 20,961 sebelum bekerja, dan rerata sebesar 32,466 ± 0,915
sesudah bekerja, sedangkan sesudah perlakuan didapat rerata 32,466 ± 0,915 sebelum bekerja dan
rerata 57,800 ± 5,634 sesudah bekerja. Sehingga terjadi penurunan keluhan subjektif sebesar
25,334% dan berbeda bermakna (p < 0,05).
PEMBAHASAN
Hasil analisis terhadap 3 orang pekerja pemotong batu padas menunjukkan bahwa rerata
umur subjek 46,00 ± 3,00 tahun, dengan rentangan umur subjek yang telah ditetapkan, yaitu antara
35 − 55 tahun. Berkaitan dengan umur bahwa kapasitas fisik seseorang berbanding langsung
sampai batas tertentu dengan umur, dan mencapai puncaknya pada umur 25 tahun.³
Beban kerja diukur berdasarkan denyut nadi pekerja melalui selisih denyut nadi kerja dan
denyut nadi istirahat. Sebelum dilakukan analisis efek perlakuan perlu dilakukan uji normalitas
terhadap data denyut nadi tersebut. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa denyut
nadi kerja tidak berdistribusi normal. Kondisi awal sebelum bekerja baik pada sebelum perlakuan
dan sesudah perlakuan dapat dikatakan tidak berbeda bermakna, namun terdapat perbedaan setelah
perlakuan baik pada denyut nadi kerja maupun nadi kerja.
KESIMPULAN DAN SARAN
Metode kerja berorientasi k3 meningkatkan kinerja dilihat dari penurunan beban kerja
3,347%, meningkatkan kinerja dilihat dari penurunan keluhan muskuloskeletal sebesar 25,33%,
meningkatkan kinerja dilihat dari penurunan kelelahan sebesar 15,934%.
Saran dari penelitian ini adalah para pekerja hendaknya dalam bekerja selalu memperhatikan
metode kerja K3 untuk menciptakan kondisi yang aman, nyaman dan sehat, serta para pengusaha
untuk memperhatikan para pekerja pada lingkungan kerja, sikap kerja dn alat kerjanya.
DAFTAR PUSTAKA
1. Solehuddin, 2009. Kreasi Unik Batu Alam, Jakarta. 2. Grandjean, E. Kroemer 2000. Fitting the Task To The Man. A Textbook of Occupational
Of Ergonomics. 4 Th Ed. London : Taylor & Francis.
3. Manuaba, A. 1998. Dengan Desain yang Aman Mencegah Kecelakaan dan Cedera. Bunga
Rampai Ergonomi: Vol I. Program Pascasarjana Ergonomi-Fisiologi Kerja, Universitas
Udayana, Denpasar.
4. Manuaba, A. 2000. Ergonomi Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Editor : Sritomo
Wignyosubroto dan Stefanus Eko Wiranto. Prosiding Seminar Nasional Ergonomi 2000 di
Surabaya. Guna Widya.
5. Hadi, S. 1995. Metodologi Reasearch Jilid IV. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 119
EVALUASI KINERJA KADER POSYANDU BAYI DAN BALITA DI
WILAYAH KERJA PUSKESMAS BANGUNTAPAN II BANTUL
Rosikhah Al-Maris,1 Pamulatsih Dwi Oktavianti
2
1Departemen Keperawatan Anak, STIKES Al Islam Yogyakarta
2Dosen STIKES Al Islam Yogyakarta
Jl. Bantul Dukuh MJ 1/1221, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
Coresponding Email : [email protected]
PERFORMACE EVALUATION OF POSYANDU CADRE FOR INFANTS AND
CHILDREN IN THE WORKING AREA OF PUSKESMAS BANGUNTAPAN II
BANTUL
ABSTRACT
Posyandu is one of the Community-Based Health Efforts (UKBM) which is the spearhead of community-
based management of infant and toddler health problems. The success of Posyandu cannot be separated from
the performance of competent Posyandu cadres. If the cadres 'performance is not optimal, it will result in
poor nutritional status and monitoring of toddlers' growth and development, as well as infant and toddler
health problems that cannot be detected early. Monitoring the growth status of children under five years in
Bantul district in 2015, 195 children were identified as experiencing less growth with the largest number
from the target area of the Puskesmas Banguntapan II Bantul. The purpose of this study was to evaluate the
performance of Infant and Toddler Posyandu cadres in the Puskesmas Banguntapan II Bantul. This research
type is quantitative descriptive with cross sectional technique. The research instrument is a questionnaire
sheet containing closed and open questions according to the material in the Curriculum Guidelines and
Posyandu Cadre Training Modules made by the Ministry of Health, plus online individual discussions.
Respondents in this study were 47 cadres who were representatives of 47 Posyandu for Infant and Toddlers
in the Puskesmas Banguntapan II Bantul. The results showed the evaluation of the performance of the Infant
and Toddler Posyandu cadres based on 7 sub-categories, namely: 1) Basic knowledge with a mean of 92.5%
(very good) performance, 2) a cadre's task with a mean of 19.1% (less), 3 ) Target’s health problems with
mean performance achievement of 61,65% (good enough), 4) Ability to move the community with Mean
performance achievement of 60.65% (good enough), 5) Implementation of five steps with Mean performance
achievement of 68.7% (quite good ), 6) Health Education with Mean 76.6% (good) performance, 7)
Recording and Reporting with Mean 77.3% (Good) performance. Based on the results of the study it can be
concluded that the performance of Posyandu cadres for infants and toddlers at the Puskesmas Banguntapan
II Bantul average is 65.21% or quite good.
Keywords: Posyandu cadres, evaluate the performance of Infant and Toddler Posyandu cadres, infant and
toddler
ABSTRAK
Posyandu merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang menjadi ujung
tombak penatalaksanaan persoalan kesehatan bayi dan balita yang berbasis masyarakat. Keberhasilan
Posyandu tidak bisa lepas dari kinerja kader Posyandu yang kompeten. Apabila kinerja kader kurang optimal,
maka berakibat status gizi dan pemantauan tumbuh kembang balita tidak terlaksana dengan baik, sekaligus
masalah kesehatan bayi dan balita tidak bisa terdeteksi secara dini. Pemantauan status pertumbuhan balita di
kabupaten Bantul tahun 2015 terdapat 195 balita teridentifikasi mengalami pertumbuhan yang kurang dengan
angka terbesar dari wilayah binaan Puskesmas Banguntapan II Bantul. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengevaluasi kinerja kader Posyandu Bayi dan Balita di wilayah kerja Puskesmas Banguntapan II Bantul.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik cross sectional. Instrumen
penelitian ini adalah lembar kuesioner yang berisi pertanyaan tertutup dan terbuka sesuai dengan materi
dalam Pedoman Kurikulum dan Modul Pelatihan Kader Posyandu yang dibuat oleh Kemenkes, serta
ditambah dengan diskusi perorangan secara daring. Responden pada penelitian ini berjumlah 47 kader yang
merupakan perwakilan dari 47 Posyandu Bayi dan Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Banguntapan II
Bantul. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi Kinerja kader Posyandu Bayi dan Balita berdasarkan 7 sub
yaitu: 1) Pengetahuan dasar dengan Mean capaian kinerja 92,5% (sangat baik), 2) Tugas kader dengan Mean
capaian kinerja 19,1% (kurang), 3) Masalah kesehatan sasaran dengan Mean capaian kinerja 61,65% (cukup
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 120
baik), 4) Kemampuan menggerakkan masyarakat dengan Mean capaian kinerja 60,65% (cukup baik), 5)
Pelaksanaan lima langkah dengan Mean capaian kinerja 68,7% (cukup baik), 6) Penyuluhan dengan Mean
capaian kinerja 76,6% (baik), 7) Pencatatan dan Pelaporan dengan Mean capaian kinerja 77,3% (Baik).
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kinerja kader Posyandu bayi dan balita di Puskesmas
Banguntapan II Bantul secara rata-rata mendapatkan nilai 65,21% atau dikatakan cukup baik.
Kata Kunci: kader posyandu, evaluasi kinerja kader posyandu, bayi dan balita
PENDAHULUAN
Kurang gizi pada anak merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di Negara
berkembang, termasuk Indonesia. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) tingginya angka
malnutrisi dan gangguan tumbuh kembang pada bayi dan balita pada periode 6-18 bulan
kehidupannya di berbagai Negara tentunya menjadi perhatian dunia, begitupun yang terjadi di
Indonesia. Menurut Data Riskesdas (2018), proporsi gizi buruk dan gizi kurang di Indonesia tahun
2018 mencapai angka 17,7%, sedangkan proporsi status gizi sangat pendek dan pendek pada
BADUTA berada di angka 29,9%.1 Faktor-faktor yang berperan pada meningkatnya angka gizi
buruk dan kegagalan tumbuh kembang adalah ketidakmampuan mencukupi kebutuhan gizi,
kurangnya stimulasi, kekurangan yodium, dan anemia defisiensi besi.2
Arah kebijakan pembangunan kesehatan yang tertuang dalam rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMN) tahun 2010-2014 menitikberatkan pada pendekatan upaya preventif, promotif,
dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Strategi pelayanan kesehatan dasar
masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak dapat dilakukan pada posyandu, karena posyandu
merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan
kesehatan dasarnya.3 Pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan primer seperti Puskesmas
merupakan salah satu pendekatan untuk mengatasi persoalan kesehatan anak yang berbasis
masyarakat.4
Pos pelayanan terpadu (posyandu) adalah salah satu Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama
masyarakat. Pelayanan kesehatan dasar di Posyandu adalah layanan kesehatan yang mencakup
sekurang-kurangnya 5 kegiatan, yaitu Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Imunisasi,
Gizi dan Penanggulangan Diare. 5
Terdapat beberapa faktor yang bisa mendukung suksesnya pelaksanaan posyandu, salah
satunya adalah kader. Peranan kader sangat penting karena kader bertanggungjawab dalam
pelaksanaan program posyandu, bila kader tidak aktif maka pelaksanaan posyandu juga akan
menjadi tidak lancar dan akibatnya status gizi balita tidak dapat dideteksi secara dini dengan jelas.6
Hal ini secara langsung akan mempengaruhi tingkat keberhasilan program posyandu khususnya
dalam memantau tumbuh kembang balita. Selain itu, melalui para kader para ibu bayi dan balita
akan mendapatkan informasi kesehatan lebih cepat. 7 Namun, keberadaan kader relatif labil karena
partisipasinya bersifat sukarela, sehingga tidak ada jaminan bahwa para kader akan tetap
menjalankan fungsinya dengan baik.8
Selain itu, kurang berfungsinya Posyandu antara lain
disebabkan karena rendahnya kemampuan kader dan pembinaan yang masih belum optimal yang
kemudian mengakibatkan rendahnya minat masyarakat berpartisipasi dalam posyandu.9
Pada tahun 2015, di Bantul tingkat partisipasi masyarakat dalam penimbangan di Posyandu
sebesar 80,61%, sehingga dapat disimpulkan bahwa masih ada balita yang tidak dibawa ke
posyandu dan tidak mendapat imunisasi sesuai waktunya. Pemantauan status pertumbuhan balita di
kabupaten Bantul tahun 2015 terdapat 195 balita teridentifikasi mengalami pertumbuhan yang
kurang dengan angka terbesar dari wilayah binaan Puskesmas Banguntapan II sejumlah 7% dan
2,4% memiliki berat badan di bawah garis merah (BGM).10
Berdasarkan fakta-fakta ini,
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 121
memunculkan pertanyaan apakah kader posyandu anak wilayah binaan Puskesmas Banguntapan II
Bantul sudah melakukan kinerja sebagaimana mestinya? Sehingga perlu dilakukannya evaluasi
untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan evaluasi terhadap kinerja kader
posyandu anak di wilayah kerja Puskesmas Banguntapan II Bantul.
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis non eksperimental dan
metode pengambilan data cross sectional survey. Model ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi
kinerja kader Posyandu bayi dan balita di lingkup kerja Puskesmas Banguntapan II Bantul yang
terdiri dari 47 posyandu dan dilaksanakan pada bulan Agustus 2020. Instrumen penelitian yang
digunakan adalah data primer yang diambil dengan menggunakan kuesioner sesuai Buku
Kurikulum dan Modul Pelatihan Kader Posyandu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang
telah divalidasi.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kader Posyandu bayi dan balita di lingkup kerja
Puskesmas Banguntapan II Bantul sejumlah 47 kader. Cara pengambilan sampel dilakukan dengan
menggunakan teknik purposive sampling, yaitu setiap Posyandu dipilih satu orang kader untuk
menjadi rsponden sehingga didapatkan besaran sebanyak 47 kader Posyandu yang mewakili setiap
Posyandu dan memenuhi kriteria inklusi penelitian.
Kriteria Inklusi penelitian antara lain: 1) pernah mendapatkan pelatihan kader posyandu; 2)
memiliki masa kerja minimal 6 bulan dan, 3) bersedia menjadi responden. Sedangkan kriteria
eksklusi penelitian ini adalah: 1) sedang melaksanakan tugas diluar kota, 2) tidak bersedia
diwawancarai.
Rencana awal pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui
kuesioner dan FGD. Namun karena terkendala dengan Pandemi Covid 19, peneliti melakukan
beberapa penyesuaian, diantaranya: 1). Penelitian yang awalnya direncanakan tatap muka namun
akhirnya dilakukan secara daring melalui google form, 2) Penguatan data yang menurut asumsi
peneliti dibutuhkan dalam beberapa poin pertanyaan untuk evaluasi kinerja Kader, yang awalnya
direncanakan didapatkan melalui FGD, akhirnya dilakukan dengan penambahan pertanyaan
terbuka dalam kuesioner serta wawancara singkat via telpon kepada respoden.
HASIL PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Banguntapan II Bantul dengan besaran sampel 47
kader Posyandu. Pengumpulan data dilakukan secara daring serentak pada hari Minggu, 16
Agustus 2020.
1. Karakteristik Responden Penelitian
Analisis univariat mendeskripsikan distribusi frekuensi untuk semua variabel penelitian
yang terdiri dari usia, pendidikan terakhir, status perkawinan, pekerjaan kader, dan lama menjadi
kader.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 122
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Variabel Penelitian Evaluasi Kinerja Kader Posyandu
Bayi dan Balita di Puskesmas Banguntapan II Bantul
Karakteristik
Responden
N Persentase
Usia Kader 1. 30-40 tahun
2. 40-50 tahun
3. 50-60 tahun
4. >60 tahun
12
18
13
4
25,6%
38,2%
27,7%
8,5% Pendidikan terakhir
1. Lulus SD
2. Lulus SMP
3. Lulus SMA 4. Lulus D3/S1/S2
0
12
25 10
0
25,5%
53,2% 21,3%
Pekerjaan Kader
1. Ibu Rumah Tangga
2. PNS 3. Swasta
40
7 0
85,1%
14,9% 0
Lama menjadi Kader Posyandu
1. 0-5 tahun
2. 5-10 tahun 3. >10 tahun
10
5 32
21,3%
10,6% 68,1%
Sumber: Data Primer, 2020
Tabel 1 menunjukkan bahwa kader Posyandu bayi dan balita pada lingkup kerja Puskesmas
Banguntapan II Bantul didominasi oleh usia 40-50 tahun (38,2%). Serta pendidikan kader rata-rata
adalah lulusan SMA(53,2%) dengan masa kerja lebih dari 10 tahun (68,1%). Kader juga
didominasi oleh ibu tumah tangga (85,1%).
2. Evaluasi Kinerja Kader Posyandu Bayi dan Balita
Tabel 2. Pengetahuan Dasar Posyandu
Pertanyaan Jawaban
benar
Jawaban
salah
Prosentase
capaian
1. Apakah kepanjangan dari Posyandu 44 3 93,6%
2. Sebutkan urutan pelaksanaan kegiatan Posyandu 38 9 80,8%
3. Siapakah sasaran dalam kegiatan Posyandu 39 8 82,9%
4. Di bawah ini yang merupakan kegiatan pelayanan Posyandu bayi dan balita adalah
47 0 100%
5. Apakah kepanjangan dari BGM 45 2 95,7%
6. Apakah yang dimaksud dengan istilah 2T pada
KMS
45 2 95,7%
7. Apakah imunisasi yang diberikan saat pertama kali
bayi lahir
41 6 87,2%
8. Kapankah pemberian imunisasi campak yang pertama
43 4 91,4%
9. ASI eksklusif diberikan sampai bayi berusia 46 1 97,8%
10. ASI yang pertama kali keluar pada saat bayi lahir dinamakan
46 1 97,8%
11. Salah satu program gizi adalah pemberian vitamin
A. Pada bulan apakah pemberian vitamin A pada balita
47 0 100%
12. Vitamin A dengan dosis 100.000 IU (warna biru)
diberikan pada balita yang berumur
41 6 87,2%
Mean capaian kinerja 92,5%
Sumber: Data Primer, 2020
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 123
Tabel 2 menunjukkan hasil penilaian terhadap kader yang berkaitan dengan pengetahuan
dasar Posyandu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui evaluasi terhadap pengetahuan dasar
Posyandu kader mendapatkan nilai rata-rata 92,5 % (Sangat baik).
Tabel 3.Tugas Kader dalam Penyelenggaraan Posyandu
Pertanyaan Jawaban
lengkap
Jawaban tidak
lengkap
Prosentase
capaian
1. Di bawah ini, mana sajakah tugas kader Posyandu
yang anda lakukan sebelum hari buka Posyandu?
7 40 14,9%
2. Di bawah ini, mana sajakah tugas kader Posyandu yang anda lakukan saat hari buka Posyandu?
9 38 19,1%
3. Di bawah ini, mana sajakah tugas kader Posyandu
yang anda lakukan setelah hari buka Posyandu?
11 36 23,4%
Mean capaian kinerja 19,1%
Sumber: Data Primer, 2020
Tabel 3 menunjukkan hasil penilaian kinerja kader terhadap pelaksanaan tugas sebelum, saat,
dan sesudah pelaksanaan kegiatan Posyandu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui nilai rata-rata
19,1 % (Kurang).
Tabel 4. Masalah Kesehatan Pada Sasaran
Sumber: Data Primer, 2020
Tabel 4 menunjukkan hasil penilaian terhadap kader yang berkaitan dengan masalah
kesehatan pada sasaran, yaitu bayi dan balita. Berdasarkan hasil penelitian diketahui evaluasi
kinerja kader terhadap masalah kesehatan pada sasaran mendapatkan nilai rata-rata 61,65 %
(Cukup baik).
Tabel 5. Kemampuan Kader Menggerakkan Masyarakat
Pertanyaan Jawaban
Pernah/
Benar/ Jumlah kasus
Jawaban
Tidak Pernah/
Salah/ Jumlah kasus
Prosentase
capaian
1. Apakah selama menjadi kader Posyandu anda pernah menemukan kasus stunting di wilayah kerja anda?
10 (21,3%)
37 (78,7%)
-
2. Sebaga kader, apakah kegiatan yang anda lakukan saat
menemukan kasus dicurigai stunting pada bayi dan
balita?
27 20 57,4%
3. Selama menjadi kader Posyandu di wilayah kerja anda,
berapa banyak kasus Diare yang anda temukan pada
bayi dan balita dalam satu tahun
0-5 kasus
(87,2%)
5-10 kasus
(12,8%)
-
4. Sebagai kader, apakah kegiatan yang sudah anda
lakukan saat menemukan kasus Diare pada bayi dan
balita?
31 16 65,9%
Mean capaian kinerja 61,65%
Pertanyaan Jawaban
Pernah/ Benar
Jawaban
Tidak Pernah/ Salah
Prosentase
capaian
1. 1. Apakah anda pernah melakukan kunjungan rumah? 47 0
100%
2. Bagaimanakah cara yang anda lakukan ketika ada
keluarga yang sering tidak menghadiri Posyandu?
10 37 21,3%
Mean capaian kinerja 60,65 %
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 124
Tabel 5 menunjukkan hasil penilaian kinerja kader dalam menggerakkan masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui nilai rata-rata kinerja kader dalam menggerakkan
masyarakat adalah 60,65 % (Cukup baik).
Tabel 6.Pelaksanaan Lima langkah Kegiatan Posyandu
Pertanyaan Jawaban
Benar/ Pernah
Jawaban
Salah/ Tidak pernah
Prosentase
capaian
3. 1. Kegiatan apakah yang dilakukan pada meja nomor 3 dalam Posyandu
40 7
85,1 %
3. Kegiatan penyuluhan saat Posyandu, dilakukan pada
meja nomor?
40 7 85,1 %
4. Selema menjadi kader Posyandu, di meja mana saja anda pernah bertugas?
17 30 36,1 %
Mean capaian kinerja 68,7 %
Sumber: Data Primer, 2020
Tabel 6 menunjukkan hasil penilaian kinerja kader dalam pelaksanaan lima langkah kegiatan
pada Posyandu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui nilai rata-rata kinerja kader adalah 68,7 %
(Cukup baik).
Tabel 7. Penyuluhan pada Kegiatan Posyandu
Pertanyaan Jawaban
Pernah/
Benar
Jawaban Tidak Pernah/
Salah
Prosentase capaian
1. 1. Apakah anda pernah memberikan penyuluhan pada meja
No.4?
36 11 76,6 %
Mean capaian kinerja 76,6 %
Sumber: Data Primer, 2020
Tabel 7 menunjukkan hasil penilaian kinerja kader dalam pelaksanaan penyuluhan saat
kegiatan Posyandu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui nilai rata-rata kinerja kader adalah 76,6
% (Baik).
Berdasarkan pertanyaan terbuka dalam kuesioner yang berbunyi, ―Apa sajakah topik
penyuluhan yang sudah pernah anda sampaikan saat pelaksanaan Posyandu bayi dan balita?‖ dari
36 responden yang menyatakan pernah memberikan penyuluhan, terdapat beberapa jawaban
diantaranya:
―Asi eksklusif, Pemberian MPASI, Stunting, Gizi seimbang‖ (14 responden)
―Asi ekslusif, Pemberian MPASI, Gizi seimbang‖ (6 responden)
―Stunting‖ (4 responden)
―Asi ekslusif, stunting, stunting, Gizi seimbang‖ (2 responden)
―Gizi seimbang‖ (2 responden)
―Pemberian MPASI‖ (2 responden)
―Asi ekslusif, Gizi seimbang, TB pada anak‖ (1 responden)
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 125
―Asi ekslusif, Pemberian MPASI, stunting‖ (1 responden)
―Asi ekslusif, stunting‖ (1 responden)
―Asi ekslusif, Gizi seimbang‖ (1 responden)
―Pemberian MPASI, stunting‖ (1 responden)
―Asi eksklusif‖ (1 responden)
Berdasarkan pertanyaan terbuka dalam kuesioner yang berbunyi, ―Apa sajakah media yang
pernah anda gunakan dalam memberikan penyuluhan?‖ dari 36 responden yang menyatakan pernah
memberikan penyuluhan, terdapat beberapa jawaban diantaranya:
―Buku‖ (14 responden)
―Poster dan buku‖ (8 responden)
―Leaflet dan buku‖ (5 responden)
―Leaflet, poster, dan buku‖ (4 responden)
―Poster, buku, dan papan‖ (3 responden)
―Hanya lisan‖ (1 responden)
―Poster, buku, dan artikel yang dibagikan di grup Whatsapp paguyuban‖ (1
responden)
Tabel 8. Pencatatan dan Pelaporan Posyandu
Pertanyaan Jawaban Pernah/
Benar
Jawaban Tidak Pernah/
Salah
Prosentase capaian
2. 1. Apakah anda pernah mendengar tentang SIP (Sistem
Informasi Posyandu) ?
38 9 80,9 %
2.Apakah yang dimaksud dengan SIP? 34 13 72,3 %
3. Apakah anda pernah menjalankan SIP di Posyandu? 37 10 78,7 %
Mean capaian kinerja 77,3 %
Sumber: Data Primer, 2020
Tabel 8 menunjukkan hasil penilaian kinerja kader dalam pencatatan dan pelaporan saat
kegiatan Posyandu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui nilai rata-rata kinerja kader adalah 77,3
% (Baik).
Berdasarkan Pertanyaan terbuka dalam kuesioner yang berbunyi, ―Apakah kendala yang
kader hadapi saat melaksanakan SIP?‖ terdapat beberapa jawaban diantaranya,
―Sering berganti formatnya‖
―Keterbatasan waktu dan SDM‖
―Belum tahu tentang SIP/belum maksimal pengetahuan yang didapatkan/masih
membutuhkan bimbingan dari pihak puskesmas‖
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 126
―Balita yang menangis/balita yang diasuh baby sitter yang kesulitan memberikan
data tumbuh kembang anak‖
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kinerja kader Posyandu bayi dan
balita di Puskesmas Banguntapan II Bantul secara rata-rata mendapatkan Mean: 65,21 atau
dikatakan cukup baik.
PEMBAHASAN
Gambaran data demografi responden dalam penelitian ini meliputi usia, pendidikan
terakhir, pekerjaan, dan lama menjadi kader Posyandu bayi dan balita. Teridentifikasinya rentang
usia kader Posyandu bayi dan balita di wilayah kerja Puskesmas Banguntapan II Bantul yang
didominasi oleh usia 40-50 tahun (38,2%) sesuai dengan Havighurts Develompental Theory yang
menyebukan bahwa usia tersebut masuk kedalam kategori usia produktif yang menitikberatkan
pada tanggungjawab kemasyarakatan. Sehingga, pada usia tersebut seseorang lebih banyak
memilih berperan aktif terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan.11
Teori ini juga didukung oleh
teori perkembangan dari Ericson yang menyatakan bahwa pada usia tersebut perkembangan
manusia berada pada fase Generativity vs self absorption. Pada tahap ini salah satu tugas
perkembangan yang ditargetkan adalah terjadinya keseimbangan antara generativitas dan stagnansi
guna mendapatkan nilai positif yaitu kepedulian terhadap masyarakat dan orang lain.12
Hasil data kuesioner menunjukkan 78,7% responden berpendidikan menengah (lulusan
SMP/SMA), dan 21,3% responden berpendidikan tinggi (lulusan D3/S1/S2). Tingkat pendidikan
merupakan salah satu dari karakteristik demografi yang disebutkan oleh Schermerhorn JR dalam
buku Organizational Behaviour sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja
seseorang.13
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan kader mayoritas adalah sebagai Ibu rumah
tangga (85,1%) dan PNS (14,9%). Berdasarkan hasil dari penelitian Etnografi tentang Posyandu
dan Ibu rumah tangga, dikatakan bahwa Posyandu meletakkan kaum perempuan, khususnya ibu
rumah tangga, sebagai ujung tombak untuk meujudkan masyarakat yang sehat, baik dari segi fisik
maupun perilaku sehari-hari. Para ibu rumah tangga tersebut tidak hanya sebagai sasaran program-
program kesehatan, tetapi juga sebagai orang yang menjalan program, yang selanjutnya disebut
Kader Posyandu.14
Dari variabel lama menjadi Kader Posyandu, sebanyak 68,1% responden sudah menjadi
kader lebih dari 10 tahun, 21,3% selama 0-5 tahun, dan 10,6% menjadi kader selama 5-10 tahun.
Koordinator Posyandu di Banguntapan mengatakan bahwa untuk mencari pengganti kader yang
sudah berusia lanjut dan menjabat lama dengan kader yang lebih muda sulit dilakukan karena calon
kader usia muda cenderung sibuk dengan pekerjaannya dan tidak mau menjadi kader dengan alasan
insentif yang tidak ada.15
Namun, menurut Simanjuntak (2012) tidak ada hubungan masa
kerja/lama menjadi kader dengan kinerja seorang kader. Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan
Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang mengatakan bahwa usia yang sudah lanjut dan
lama menjabat sebagai kader bukan menjadi persoalan karena penyuluhan dan pelatihan dari
puskesmas dan dinas rutin dilakukan kepada para kader, sehingga diharapkan tidak mengganggu
kinerja kader Posyandu.15
Pada hasil evaluasi kinerja Kader Posyandu bayi dan balita di wilayah kerja Puskesmas
Banguntapan II Bantul, yang terdiri dari tujuh tolak ukur berdasarkan buku Kurikulum dan Modul
Pelatihan Kader Posyandu yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan RI, yaitu: 1) Pengetahuan
dasar Posyandu, 2) Tugas Kader dalam penyelenggaraan Posyandu, 3) Masalah kesehatan pada
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 127
sasaran, 4) Kemampuan Kader menggerakkan masyarakat, 5) Pelaksanaan lima langkah kegiatan
Posyandu, 6) Penyuluhan pada kegiatan Posyandu, 7) Pencatatan dan pelaporan Posyandu.17
Pengetahuan dasar Posyandu
Berdasarkan hasil dari penelitian, pengetahuan dasar Posyandu pada Kader Posyandu bayi
dan balita di wilayah kerja Puskesmas Banguntapan II Bantul mendapatkan nilai rata-rata 92,5%
(sangat baik). Pengetahuan dasar terhadap pengelolaan Posyandu menjadi salah satu tolak ukur
baik tidaknya kinerja Kader. Aktif tidaknya kinerja kader salah satunya dipengaruhi oleh
pengetahuan terhadap pengelolaan Posyandu.18
Berdasarkan 12 pertanyaan tentang pengetahuan dasar pengelolaan Posyandu, prosentase
jawaban benar tertinggi ada pada pertanyaan-pertanyaan mengenai program gizi, diantaranya: 1)
Jadwal pemberian vitamin A, yaitu dari 47 responden 100% mampu menjawab dengan benar, 2)
Pemberian ASI ekslusif dan kolostrum, yaitu dari 47 responden terdapat 4 responden (97,8%)
mampu menjawab dengan benar. Hal ini menjadi indikator bahwa pengetahuan dasar Kader
Posyandu Bayi dan Balita di wilayah kerja Puskesmas Banguntapan II Bantul sudah sangat baik.
Pelayanan gizi adalah salah satu kegiatan Posyandu yang selalu dilakukan setiap bulan sekali.
Pelayanan gizi di Posyandu dilakukan oleh kader yang bentuk pelayanannya meliputi penimbangan
berat badan, pengisian KMS, deteksi dini gangguan pertumbuhan, penyuluhan gizi, pemberian
PMT, pemberian vitamin A dan pemberian sirup besi (Fe).19,20
Tugas Kader dalam penyelenggaraan Posyandu
Dalam penyelenggaraan Posyandu terdapat tiga tahapan, yaitu sebelum hari buka
Posyandu, saat hari buka Posyandu, dan setelah hari buka Posyandu. Berdasarkan hasil penelitian
yang disajikam pada Tabel 3, penilaian kinerja Kader dalam penyelenggaraan Posyandu
mendapatkan nilai rata-rata 19,1 % (Kurang). Tugas Kader sebelum hari buka Posyandu atau
disebut juga tugas pada H-Posyandu adalah tugas-tugas persiapan yang dilakukan oleh Kader agar
kegiatan pada hari buka Posyandu berjalan dengan baik. Tugas-tugas pada H-1 Posyandu terdiri
dari: a) Melakukan persiapan penyelengaraan kegiatan Posyandu, b) Menyebarluaskan informasi
tentang hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat atau surat edaran, c) Melakukan
pembagian tugas antar Kader, meliputi Kader yang menangani pendaftaran, penimbangan,
pencatatan, penyuluhan, pemberian makanan tambahan, serta pelayanan yang dapat dilakukan oleh
Kader, d) Kader melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan atau petugas lainnya, e)
Menyiapkan bahan pemberian makanan tambahan (PMT) serta penyuluhan sesuai dengan
permasalahan yang ada dan dihadapi oleh para orangtua bayi dan balita wilayah binaan, f)
Menyiapkan buku-buku catatan kegiatan Posyandu.17
Berdasarkan hasil penelitian, dari 47
responden hanya 7 responden yang menjalankan tugas H-1 Posyandu secara lengkap (14,9%), 15
responden tidak memilih opsi pendekatan tokoh masyarakat baik formal maupun informal dan
menghubungi pokja Posyandu (koordinasi dengan petugas lain), dan 6 responden lainnya tidak
memilih opsi menyiapkan PMT sebagai kegiatan yang mereka lakukan pada H-1 Posyandu.
Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa ada 1 responden yang pada H-1 Posyandu hanya
pernah melakukan tugas Kader berupa menyiapkan sarana dan prasarana di tempat Posyandu.
Berdasarkan temuan data tersebut, perlu diberikan rekomendasi agar dilakukan pelatihan ulang
untuk memaparkan secara lengkap tugas kader H-1 Posyandu.
Tugas Kader pada hari buka Posyandu atau disebut juga pada H Posyandu adalah berupa
tugas-tugas untuk melaksanakan pelayanan 5 kegiatan yang terdiri dari: a) Melakukan pendaftaran,
meliputi pendaftaran balita, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui dan sasaran lainnya, b) Pelayanan
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 128
kesehatan pada anak Posyandu diantaranya: penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan,
pengukuran lingkar kepala anak, deteksi perkembangan anak, pemantauan status imunisasi anak,
pemantauan terhadap tindakan orangtua tentang pola asuh, pemantauan permasalahan bayi dan
balita, c) Membimbing orangtua melakukan pencatatan terhadap berbagai hasil pengukuran dan
pemantauan kondisi bayi dan balita, d) Melakukan penyuluhan, e) Menyampaikan penghargaan
kepada orang tua yang telah datang ke Posyandu dan minta mereka untuk kembali pada hari
Posyandu berikutnya.17
Berdasarkan hasil penelitian, dari 47 responden hanya 9 responden (19,1%)
yang menjalankan tugas H Posyandu secara lengkap. Tugas pada H Posyandu yang paling banyak
terlewat dan belum dilaksanakan adalah: Pemberian penyuluhan atau konseling, pemberian oralit,
tablet zat besi dan vitamin A, pencatatan kegiatan Posyandu, dan pemberian rujukan.
Tugas sesudah hari buka Posyandu atau disebut juga tugas pada H+ Posyandu, yaitu berupa
tugas-tugas setelah hari Posyandu, yang terdiri dari: a) Melakukan kunjungan rumah pada balita
yang tidak hadir pada hari buka Posyandu, pada anak yang kurang gizi dll, b) Memotivasi
masyarakat untk memanfaatkan pekarangan dalam rangka meningkatkan gizi keluarga, menanam
obat keluarga, membuat tempat bermain anak yang nyaman. Selain itu, memberikan penyuluhan
agar mewujudkan rumah sehat, bebas jentik, kotoran, sampah, asap rokok dll, c) Melakukan
pertemuan dengan tokoh masyarakat, pimpinan wilayah untuk menyampaikan atau
menginformasikan hasil kegiatan Posyandu, d) Membuat laporan SIP dan melaporkan pada
Posyandu.17
Berdasarkan hasil penelitian, dari 47 responden hanya 11 responden (23,4%) yang
menjalankan tugas H+1 Posyandu secara lengkap. Tugas H+1 yang paling banyak terlewat adalah
diskusi kelompok dan pelaksanaan kunjungan rumah pada ibu bayi dan balita yang tidak hadir
dalam kegiatan Posyandu.
Penilaian Masalah kesehatan pada sasaran
Masalah kesehatan pada bayi dan balita seperti yang disebutkan dalam Buku Pedoman
Kader terdiri dari: Balita kurang gizi, diare, kerdil, lumpuh (polio), batuk, tetanus, campak, sakit
kulit, saki gigi dll.17
Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat dua masalah yaitu stunting dan
diare. Stunting (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang
kurang jika dibandingkan dengan umur. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang
disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada
bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi.21
Rata-rata prevalensi balita stunting di regional Asia
Tenggara tahun 2017, Indonesia menempati peringkat 3 tertinggi setelah Timor Leste dan India.22
Berdasarkan hasil penelitian diketahui evaluasi kinerja kader terhadap masalah kesehatan pada
sasaran mendapatkan nilai rata-rata 61,65 % (Cukup baik). Dari 47 responden yang berasal dari 47
posyandu berbeda di wilayah kerja Puskesmas Banguntapan II Bantul, 10 responden (21,3%)
menjawab pernah menemukan kasus stunting di wilayah kerjanya. Berdasarkan pertanyaan
kuesioner selanjutnya, 27 responden (57,4%) mampu memberikan jawaban yang benar mengenai
tatalaksana yang bisa kader Posyandu lakukan saat menemukan kasus stunting di wilayah kerjanya.
Berdasarkan hasil penilaian kuesioner, 20 responden lainnya cenderung hanya memilih jawaban
melaporkan atau memberikan rujukan kepada puskesmas ketika menemui kasus stunting. Padahal,
masih ada tatalaksana lain yang bisa dilakukan sebagai seorang kader seperti: pembinaan dalam
pemberian makanan bergizi seimbang, penyuluhan pentingnya ASI ekslusif, dan melakukan
penyuluhan menu dan saat memulai MPASI yang tepat.
Penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Negara berkembang
seperti di Indonesia.23
Bila dilihat dari kelompok umur diare tersebar di semua kelompok umur
dengan prevalensi tertinggi pada anak balita usia 1-4 tahun yaitu 16,7%. Prevalensi diare juga lebih
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 129
tinggi di pedesaan dibandingkan perkotaan yaitu 10% dibanding 7,4%. Dari 47 responden,
sejumlah 41 responden (87,2%) menjawab menemukan kasus diare pada wilayah kerjanya
sebanyak 0-5 kasus dalam satu tahun, sedangkan 6 responden (12,8%) melaporkan temuan 5-10
kasus diare dalam kurun waktu satu tahun. Berdasarkan pertanyaan kuesioner selanjutnya, 31
responden (65,9%) mampu memberikan jawaban yang benar mengenai tatalaksana yang bisa kader
Posyandu lakukan saat menemukan kasus diare di wilayah kerjanya. Berdasarkan hasil penilaian
kuesioner, 16 responden lainnya masih beranggapan bahwa tatalaksana yang bisa dilakukan saat
menemukan kasus diare hanya dengan memberikan rujukan ke puskesmas, lalu ada responden yang
hanya menganjurkan pemberian ASI lebih sering dan banyak pada bayi dan balita. Berdasarkan
hasil penelitian diketahui evaluasi kinerja kader terhadap masalah kesehatan pada sasaran
mendapatkan nilai rata-rata 61,65 % (Sedang).
Kemampuan Kader menggerakkan masyarakat
Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan kader sebelum hari buka Posyandu adalah
menggerakkan masyarakat kemudian kunjungan rumah yang dilakukan setelah hari buka
Posyandu.17
Peran kader dalam penyelenggaraan Posyandu sangat besar karena selain sebagai
pemberi informasi kesehatan kepada masyarakat juga sebagai penggerak masyarakat untuk datang
ke Posyandu dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.24
Berdasarkan hasil penelitian
diketahui nilai rata-rata kinerja kader dalam menggerakkan masyarakat adalah 60,65 % (Cukup
baik). Dari 47 responden, diperoleh data bahwa 100% kader menjawab pernah melakukan
kunjungan rumah. Kunjungan rumah adalah salah satu kegiatan kader Posyandu yang bertujuan
untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat tentang kegiatan di Posyandu dan manfaatnya.17
Pada pertanyaan selanjutnya tentang cara yang dilakukan kader ketika menghadapi
persoalan keberadaan keluarga yang sering tidak menghadiri kegiatan Posyandu, dari 47 responden
hanya 10 responden (21,3%) yang menjawab sesuai dengan buku pedoman kader. 22 (46,8%)
responden lainnya tidak melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat sebagai upaya
menggerakkan keaktifan masyarakat dalam mengikuti Posyandu. Dalam sebuah penelitian tentang
Hubungan Peran Petugas Kesehatan, Tokoh Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat dalam
Pelaksanaan Posyandu, ditemukan hasil bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi
pasrtisipasi masyarakat adalah peran tokoh masyarakat. Sehingga diharapkan petugas kesehatan
dalam hal ini adalah kader, dapat melakukan diskusi rutin dengan tokoh masyarakat untuk
meningkatkan peran tokoh masyarakat.25
Pelaksanaan lima langkah kegiatan Posyandu
Kegiatan rutin Posyandu diselenggarakan dan digerakkan oleh kader Posyandu dengan
bimbingan teknis dari Puskesmas dan sektor terkait. Pada saat penyelenggaraan Posyandu, minimal
jumlah Kader adalah lima orang. Jumlah ini sesuai dengan jumlah lima langkah yang dilaksanakan
oleh Posyandu. Rincian kegiatan lima langkah di Posyandu diantaranya: 1) Pendaftaran, 2)
Penimbangan, 3) Pengisian KMS, 4) Penyuluhan, 5) Pelayanan kesehatan.17
Berdasarkan hasil
penelitian, diketahui nilai rata-rata kinerja kader dalam pelaksanaan lima langkah kegiatan
Posyandu adalah 68,7 % (Cukup baik). Berdasarkan hasil penelitian, dari 47 responden terdapat 17
responden (36,1%) yang pernah menjalankan meja 1,2,3 dan 4 selama menjadi kader, sedangkan 30
responden lainnya baru menjalankan 2 hingga 3 meja. Sebagai seorang kader Posyandu yang sudah
mendapatkan pelatihan, diharapkan kader mampu menjalankan seluruh meja agar mendapatkan
pengalaman pada masing-masing meja.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 130
Penyuluhan pada kegiatan Posyandu
Penyuluhan merupakan penyampaian pesan dari satu orang atau kelompok kepada satu
orang atau kelompok lain mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan suatu program. Salah satu
pelatihan yang dilakukan pada setiap kader adalah membekali para Kader Posyandu agar dapat
memberikan penyuluhan dalam kegiatan Posyandu maupun di luar kegiatan Posyandu. Selain itu,
diharapkan kader Posyandu mampu menggunakan pesan, memilih metode dan media penyuluhan
yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pesan yang disampaikan kepada masyarakat dapat
diterima dan dimengerti.17
Berdasarkan hasil penelitian diketahui nilai rata-rata kinerja kader dalam
melaksanakan penyuluhan adalah 76,6 % (Baik).
Dari 47 responden, terdapat 11 responden (23,4%) yang belum pernah memberikan
penyuluhan pada meja 4. Padahal, kader diharapkan berperan aktif dan mampu menjadi pendorong,
motivator dan penyuluh masyarakat. Kader diharapkan dapat menjembatani antara petugas/ahli
kesehatan dengan masyarakat serta membantu masyarakat mengidentifikasi dan
menghadapi/menjawab kebutuhan kesehatan mereka sendiri.26
Terdapatnya 11 responden yang
menyatakan belum pernah memberikan penyuluhan tentu bisa menjadi rekomendasi pada
rancangan program pelatihan kader selanjutnya agar lebih ditekankan kembali tentang peran
penyuluhan kesehatan yang diharapkan dari kader Posyandu bayi dan balita, sekaligus pelatihan
tentang cara berkomunikasi efektif guna meningkatkan kepercayaan diri kader untuk tampil
memberikan penyuluhan pada sasaran.
Pertanyaan selanjutnya adalah tentang pemilihan media yang digunakan kader dalam
pelaksanaan Posyandu. Dari 36 responden yang pernah memberikan penyuluhan, 14 responden
(38,8%) hanya menggunakan buku, lalu 8 responden (22,2%) menggunakan poster dan buku, dan 5
responden (13,8%) menggunakan leaflet dan buku. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan
bahwa media yang paling banyak digunakan dalam penyuluhan kader adalah buku. Media
penyuluhan adalah alat bantu dalam melakukan penyuluhan agar proses belajar dalam penyuluhan
menjadi lebih menarik serta mudah dilaksanakan. Berbagai bentuk media ini antara lain adalah:
buku, lembar balik, kartu konseling, poster, booklet, brosur, lembar simulasi, lembar kasus, komik
dll.17
Indikator keberhasilan dalam pemilihan media penyuluhan adalah penyaji nyaman dalam
menyampaikan materi dan audiens bisa memahami materi yang disampaikan. Dalam menggunakan
media, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu media harus mudah dimengerti oleh masyarakat
dan idea tau gagasan yang terkandung di dalamnya harus dapat diterima oleh sasaran.27
Pencatatan dan pelaporan Posyandu
Hasil penelitian menunjukkan penilaian kinerja kader dalam pencatatan dan pelaporan saat
kegiatan Posyandu mendapatkan nilai rata-rata 77,3 % (Baik). Ketersediaan data dan informasi
yang akurat diperlukan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dalam upaya pengembangan
Posyandu. Dengan demikian para kader dipandang perlu untuk dibekali dengan pengetahuan dan
kemampuan yang memadai tentang pencatatan dan pelaporan kegiatan di Posyandu dengan
menggunakan Sistem Informasi Posyandu (SIP).17
Berdasarkan hasil penelitian, 38 responden
(80,9%) pernah mendengar tentang SIP dengan 34 responden (72,3%) mengetahui definisi dari
SIP. Terdapat 37 responden (78,7%) yang pernah menjalankan SIP sebagai rangkaian pelaksanaan
Posyandu, dan 10 responden lainnya menjawab belum pernah. Berdasarkan wawancara singkat,
responden mengeluhkan beberapa kendala dalam menjalankan SIP, diantaranya: format yang sering
berubah, keterbatasan waktu dan SDM, sudah lupa cara penggunaannya, meminta untuk
didampingi lagi oleh petugas dan lain sebagainya.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 131
Dalam rangka mendukung peran Posyandu dalam memantau kesehatan ibu dan anak, maka
dibuat SIP. Di dalam SIP terdapat format pengisian catatan ibu hamil, kelahiran, kematian bayi,
dan kematian ibu hamil, melahirkan atau nifas, format pengisian register bayi dan balita, format
pengisian WUS-PUS, format pengisian data Posyandu, dan data hasil Posyandu.28
Sehingga proses
pencatatan dan pelaporan Posyandu akan memberikan kontribusi yang besar dalam pemantauan
kesehatan sasaran, dalam hal ini adalah ibu, bayi dan balita. Pada evaluasi kinerja pencatatan dan
pelaporan kader Posyandu bayi dan balita di wilayah kerja Puskesmas Banguntapan II Bantul yang
mendapatkan nilai rata-rata 77,3% (baik) masih harus ditingkatkan melihat hasil penelitian yang
menunjukkan masih ada 13 responden yang belum mengetahui SIP dan 10 responden yang belum
pernah menjalankan SIP.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Kinerja kader
Posyandu bayi dan balita di Puskesmas Banguntapan II Bantul secara rata-rata dikatakan cukup
baik. Berdasarkan tujuh tolak ukur penilaian kinerja kader Posyandu, yang terdiri dari:
1. Pengetahuan dasar pengelolaan Posyandu dikatakan sangat baik, hal ini terbukti dengan kader
yang mampu menjawab dengan benar sub pertanyaan mengenai pengetahuan dasar pengelolaan
Posyandu. Kader bayi dan balita di wilayah kerja Puskesmas Banguntapan II Bantul secara
optimal juga telah mengetahui pengetahuan-pengetahuan dasar terkait persoalan gizi pada bayi
dan balita.
2. Tugas kader dalam penyelenggaraan Posyandu dikatakan kurang karena masih banyak tugas
kader pada H-Posyandu, H Posyandu, dan H+Posyandu yang belum dijalankan oleh kader,
diantaranya: pendekatan pada tokoh masyarakat, menghubungi pokja Posyandu, menyiapkan
PMT, pemberian penyuluhan, pencatatan kegiatan Posyandu, diskusi kelompok, dan
pelaksanaan kunjungan rumah.
3. Penilaian masalah kesehatan pada sasaran dikatakan cukup baik, namun pada masalah kesehatan
seperti stunting dan diare kader belum mampu menyebutkan semua tatalaksana yang bisa
diedukasikan pada sasaran. Pada kasus stunting, kader hanya memilih tatalaksana melaporkan
atau memberikan rujukan kepada puskesmas ketika menemui kasus stunting. Padahal, masih ada
tatalaksana lain yang bisa dilakukan sebagai seorang kader seperti: pembinaan dalam pemberian
makanan bergizi seimbang, penyuluhan pentingnya ASI ekslusif, dan melakukan penyuluhan
menu dan saat memulai MPASI yang tepat. Pada diare, kader juga masih beranggapan bahwa
tatalaksana yang bisa dilakukan saat menemukan kasus hanya dengan memberikan rujukan ke
puskesmas, lalu ada responden yang hanya menganjurkan pemberian ASI lebih sering dan
banyak pada bayi dan balita.
4. Kemampuan menggerakkan masyarakat dikatakan cukup baik karena berdasarkan hasil
penelitian, semua kader pernah melakukan kunjungan rumah. Namun, terdapat temuan bahwa
kader belum melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat sebagai upaya menggerakkan
keaktifan masyarakat.
5. Pelaksanaan lima langkah kegiatan di Posyandu dikatakan cukup baik karena kader sudah
mengetahui prinsip pelaksanaan lima langkah atau lima meja dalam Posyandu. Namun, terdapat
temuan bahwa hanya 17 responden yang pernah menjalankan keseluruhan meja 1,2,3, dan 4;
sedangkan lainnya cenderung absen pada meja no.4 (penyuluhan).
6. Evaluasi kinerja penyuluhan kader dikatakan baik, dibuktikan dengan sudah mampunya kader
melaksanakan penyuluhan dan memilih media penyuluhan yang tepat. Namun, terdapat temuan
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 132
bahwa masih ada kader yang belum pernah melakukan penyuluhan selama menjadi kader
Posyandu.
7. Pencatatan dan Pelaporan dikatakan baik terbukti dengan sudah baiknya pemahaman kader
terhadap SIP dan sudah menjalankan sistem tersebut di Posyandu masing-masing. Namun,
masih ada kader yang membutuhkan pembinaan dan pelatihan ulang terhadap penggunaan SIP
karena mengaku belum paham dan sudah lupa.
Saran
Terdapat beberapa saran yang bisa direkomendasikan berdasarkan temuan hasil penelitian,
diantaranya adalah:
1. Pengetahuan dasar pengelolaan Posyandu pada kader Posyandu anak dan balita di wilayah kerja
Puskesmas Banguntapan Bantul yang dinilai sangat baik perlu untuk dipertahankan. Upgrade
pengetahuan dan skill pengelolaan Posyandu juga tetap harus rutin diadakan melalui pembinaan,
pelatihan, dan penyuluhan oleh Puskesmas.
2. Evaluasi tugas kader dalam penyelenggaraan Posyandu dinilai masih kurang dan perlu untuk
ditingkatkan.. Dalam penyelenggaraan Posyandu, tugas kader yang terdiri dari H-Posyandu, H
Posyandu, dan H+Posyandu yang sesuai dengan pedoman sekiranya perlu untuk disampaikan
kembali pada saat pertemuan rutin bersama kader.
3. Evaluasi tugas kader dalam menilai masalah kesehatan pada sasaran dikatakan cukup baik dan
masih bisa untuk ditingkatkan. Diharapkan kader Posyandu bayi dan balita dapat mendapatkan
penyuluhan mengenai masalah-masalah kesehatan yang sering terjadi pada sasaran beserta
tatalaksana awal yang dapat kader sampaikan pada sasaran sesuai dengan kompetensinya.
Bagaimanapun, kader adalah kelompok yang paling dekat dari masyarakat yang mampu
memberikan, meneruskan, dan melaporkan informasi terkait masalah kesehatan sasaran.
4. Kemampuan menggerakkan masyarakat pada kader dinilai cukup baik, namun harus bisa
ditingkatkan. Kader perlu untuk diarahkan agar mampu menggerakkan masyarakat dengan
berbagai pendekatan, baik langsung maupun tidak langsung. Usaha menggerakkan masyarakat
agar lebih aktif ikut serta dalam Posyandu secara tidak langsung adalah dengan melakukan
pendekatan pada tokoh masyarakat.
5. Evaluasi pelaksanaan lima langkah kegiatan di Posyandu mendapatkan penilaian cukup baik.
Dalam upaya membuat kemampuan kader merata dalam penguasaan meja 1,2,3, dan 4 maka
perlu dibuat jadwal perputaran jaga meja untuk semua kader yang bertugas.
6. Evaluasi penyuluhan kader di wilayah kerja Puskesmas Banguntapan II Bantul dikatakan baik,
namun berdasarkan temuan penelitian masih ada kader yang belum pernah melakukan
penyuluhan saat Posyandu. Direkomendasikan selanjutnya saat pelatihan kader agar lebih
ditekankan kembali tentang peran penyuluhan kesehatan yang diharapkan dari kader Posyandu
bayi dan balita, sekaligus pelatihan tentang cara berkomunikasi efektif guna meningkatkan
kepercayaan diri kader untuk tampil memberikan penyuluhan pada sasaran. Upgrade informasi
terkini terkait topik-topik kesehatan yang sedang terkini juga penting untuk rutin dilaksanakan
agar bisa menjadi bahan penyuluhan kader kepada masyarakat. Selain itu, pelatihan
pemanfaatan dan pencarian media penyuluhan juga bisa dilakukan.
7. Evaluasi pencatatan dan pelaporan kader Posyandu dinilai baik dan masih berpotensi untuk terus
ditingkatkan. Praktek pelaksanaan SIP masih membutuhkan pembinaan dan pelatihan dari
Puskesmas setempat agar kader bisa semakin memahami SIP dan mampu mempraktekkannya.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 133
DAFTAR PUSTAKA
1. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI tahun 2018.
2. WHO fact sheet No.178, updated September 2013. Children: reducing mortality. Diunduh
dari
3. Kemenkes RI. 2018. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Posyandu. Kementerian Kesehatan RI:
Jakarta.
4. Kementerian Kesehatan. 2011. Pedoman umum pengelolaan Posyandu. Kementerian
Kesehatan
5. Kemenkes RI. 2015. Infodatin pusat data dan informasi kementerian kesehatan RI. Jakarta:
Pusat Data dan Informasi.
6. Ismarawanti. 2010. Kader Posyandu: Peranan dan Tantangan Pemberdayaan dalam Usaha
Peningkatan Gizi Anak di Indonesia. http://download.portalgaruda.org/article. Diakses pada
tanggal 19 Maret 2020.
7. Andira, R.A., z.Abdullah, dan D. Sidik. 2012. Faktor-faktor yang berhubungan dengan
kinerja kader posyandu di Kec. Bontobahari kabupaten Bulukumba. Jurnal ilmu kesehatan
masyarakat. Unhas Makassar.
8. Wisnuwardani. 2012. Insentif Uang Tunai dan Peningkatan Kinerja Kader Posyandu,
Universitas Mulawarman, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Volume 7 No 1 Agustus
2012.
9. Legi, N.N., Rumagit, F., Montol, A.B., & Lule, R. 2015. Faktor yang berhubungan dengan
keaktifan kader posyandu di wilayah kerja Puskesmas Ranotana Weru. Jurnal GIZIDO, 7(2),
429-436.
10. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bantul. 2015. Profil Kesehatan Kabupaten Bantul.
11. Havighurst, Robert, J. 1953. Human Development and Aging Fifth Edition. New York: Mc
Graw Hill.
12. Erikson, Erick. H. 1989. Identitas dan Siklus Hidup Manusia. Bunga Rampai Penerjemah:
Agis Cremers. Jakarta: PT Gramedia.
13. French R. Organizational behaviour. Wiley;2011. 689 p
14. Wicaksono, Arif Muchammad. 2017. Ibuisme Masa Kini: Suatu Etnografi tentang Posyandu
dan Ibu Rumah Tangga. Umbara: Indonesian Journal of Anthropology, Volume 1 (2)
Desember 2016.
15. Solopos: Kaderisasi Posyandu di Jogja Macet.
https://www.google.com/amp/s/m.solopos.com/kaderisasi-posyandu-di-jogja-macet-
329250/amp. Diakses pada 02 Oktober 2020.
16. Simanjuntak M. Karakteristik Sosial Demografi dan Faktor Pendorong Peningkatan Kinerja
Kader Posyandu. JWEM (Jurnal Wira Ekon Mikroskil). 2012;2 (1):49-58.
17. Kemenkes RI. 2012. Kurikulum dan Modul Pelatihan Kader Posyandu. Kementerian
Kesehatan RI: Jakarta
18. Rahayu, S.P. 2017. Hubungan Tingkat Pengetahuan Kader Tentang Pengukuran
Antropometri Dengan Ketrampilan Dalam Melakukan Pengukuran Pertumbuhan Balita di
Posyandu Kelurahan Karangasem Kecamaan Laweyan. Skripsi: Program studi S1
Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
19. Hara, M. K., Adhi, K.T., & Pangkahila, A. 2014. Pengetahuan Kader dan Perilaku Asupan
Nutrisi Berhubungan dengan Perubahan Status Gizi Balita , Puskesmas Kawangu, Sumba
Timur. Public Health and Preventive Medicine Archive, 2(1), 33.
20. Mulat, T.C. 2017. Peran Kader Posyandu Terhadap Upaya Peningkatan Status Gizi Balita (3-
5) Tahun Di Wilayah Kerja Puskesmas Batua Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi
Husada, 5(1), 9-24.
21. Kementerian Kesehatan. 2018. Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia. Buletin Jendela
Pusat Data dan Informasi: Semester 1, 2018. ISSN 2088-270 X.
22. WHO. 2018. Child Stunting Data Visualizations Dashboard.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 134
23. Kementerian Kesehatan. 2011. Situasi Diare di Indonesia. Buletin Jendela Pusat Data dan
Informasi: Triulan II, 2011. ISSN 2088-270 X.
24. Husniyawati, Y.R., & Wulandari, R.D. 2016. Analisis Motivasi Terhadap Kinerja Kader
Posyandu Berdasarkan Teori Victor Vroom. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia,
02(03), 232-241.
25. Yuliantina, Dini., Mursyid, Abidillah. Hubungan Peran Petugas Kesehatan, Tokoh
Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat (D/S) dalam Pelaksanaan Posyandu di Kabupaten
Pandeglang Propinsi Banten. Tesis: S2 Kesehatan Masyarakat UGM.
http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/53255
26. Iswarawanti, Nastiti Dwi. 2010. Kader Posyandu: Peranan dan Tantangan Pemberdayaannya
dalam Usaha Peningkatan Gizi Anak di Indonesia. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan,
13(04),169-173.
27. Departemen Kesehatan RI. 2008. Pusat promosi kesehatan, panduan penyuluhan komunikasi
perubahan perilaku, untuk KIBBLA, Jakarta.
28. Nugroho. 2010. Hubungan antara pengetahuan dan motivasi kader Posyandu dengan
keaktifan kader Posyandu di Desa Dukuh Tengah Kecamatan Brebes.
http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/FIKkeS/article/view/221
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 135
IDENTIFIKASI KEJADIAN HIPERTENSI DAN OBESITAS SENTRAL PADA
PRA LANSIA
Yeni,
1 Fenny Etrawati,
2 Feranita Utama
3
1Bagian Biostatistik dan Sistem Informasi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Sriwijaya 2Bagian Promosi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya
3Bagian Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya
Jl. Palembang Prabumulih KM. 32, Indralaya Indah Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan
Corresponding Email : [email protected]
IDENTIFICATION OF HYPERTENSION EVENTS AND CENTRAL OBESITY IN
PRESENTS
ABSTRACT
At this time there has been an increase in the prevalence of non-communicable diseases in Indonesia,
including cancer, stroke, chronic kidney disease and hypertension. In Ogan Ilir Regency, it is known that the
prevalence of hypertension based on the measurement of blood pressure reached 31.72%. This study aims to
identify the incidence of central hypertension and obesity in pre-elderly in Indralaya Utara District, Ogan
Ilir Regency. The research design was cross sectional. The sample inclusion criteria were residents but in
Ogan Ilir who were 45 to 59 years old. The sample size used in this study was 150 people. The data analysis
used was univariate analysis to see the frequency distribution of respondent characteristics, hypertension
and central obesity. The results showed that the percentage of hypertension in pre-elderly was 34% and the
incidence of central obesity was 73.3%. Men in pre-elderly have more hypertension, while more women
suffer from central obesity. The importance of increasing education about the risk factors for hypertension
and central obesity to the pre-elderly age group.
Keywords: Hypertension, central obesity, pre elderly
ABSTRAK
Pada saat ini telah terjadi peningkatan prevalensi kejadian penyakit tidak menular di Indonesia meliputi
kanker, stroke, penyakit ginjal kronis dan hipertensi. Di Kabupaten Ogan Ilir diketahui bahwa prevalensi
hipertensi berdasarkan hasil pengukuran terhadap tekanan darah mencapai 31,72%. Penelitian ini bertujuan
untuk mengidentifikasi kejadian hipertensi dan obesitas sentral pada pra lansia di Kecamatan Indralaya Utara
Kabupaten Ogan Ilir. Desain penelitian ini adalah cross sectional. Kriteria inklusi sampel adalah penduduk
tetapi di Ogan Ilir yang berusia 45 sampai 59 tahun. Besar sampel yang digunakan pada penelitian ini
sebanyak 150 orang. Analisis data yang digunakan adalah analisa univariat untuk melihat distribusi frekunesi
karakteristik responden, hipertensi dan obesitas sentral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase
kejadian hipertensi pada pra lansia sebesar 34% dan kejadian obesitas sentral sebesar 73,3%. Laki-laki pada
usia pra lansia lebih banyak menderita hipertensi sedangkan perempuan lebih banyak yang menderita
obesitas sentral. Pentingnya meningkatkan edukasi mengenai faktor risiko hipertensi dan obesitas sentral
kepada kelompok usia pra lansia.
Kata Kunci: Hipertensi, obesitas sentral, pra lansia
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 136
PENDAHULUAN
Beberapa prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia mengalami peningkatan
berdasarkan hasil Riskesdas 2018 yaitu kanker, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes melitus, dan
hipertensi..1 Hipertensi disebut sebagai ―the silent killer‖ karena dampaknya yang mengakibatkan
tingkat morbiditas dengan penanganan serius dan mortilitas yang cukup tinggi.2 Case fatalitiy rate
(CFR) penyakit hipertensi di Indonesia mencapai 6,8% menjadikannya sebagai penyebab kematian
ketiga terbanyak di Indonesia pada semua kelompok umur.3
Menurut data Riskesdas 2018, persentase hipertensi di Indonesia berdasarkan hasil
pengukuran tekanan darah mencapai 34,1%.1 Prevalensi kejadian hipertensi meningkat seiring
meningkatnya usia seseorang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa persentase hipertensi pada
kelompok umur 18 – 40 tahun sebesar 35,2% dan meningkat pada kelompok usia >40 tahun
mencapai 93,1%.4 Prevalensi hipertensi di Provinsi Sumatera Selatan pada kelompok umur pra
lansia telah melebihi angka kejadian hipertensi secara nasional yaitu 40,91% pada kelompok umur
45 tahun sampai 54 tahun dan sebesar 54,08% pada kelompok umur 55 tahun sampai 64 tahun.
Sedangkan di Kabupaten Ogan Ilir diketahui bahwa prevalensi hipertensi berdasarkan hasil
pengukuran terhadap tekanan darah mencapai 31,72%.5
Faktor risiko hipertensi terdiri dari faktor penyebab yang dapat dimodifikasi (diet, obesitas,
merokok, dan penyakit DM) dan faktor penyebab yang tidak dapat dimodifikasi (usia, ras, jenis
kelamin dan genetik).2
Konsumsi tembakau dan alkohol, kelebihan berat badan dan obesitas sentral
juga memiliki hubungan dengan kejadian hipertensi.6 Penyakit kardiovaskuler seperti hipertensi
dan diabetes adalah penyakit utama yang disebabkan oleh obesitas.7 Hasil penelitian terdahulu
menunjukkan bahwa seseorang dengan usia pra lansia yang memiliki obesitas sentral akan berisiko
2,53 kali lebih besar mengalami kejadian hipertensi dibandingkan seorang pra lansia yang tidak
memiliki obesitas sentral.8 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kejadian obesitas sentral
dan hipertensi pada kelompok pra lansia di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.
METODE
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik secara kuantitatif. Desain
penelitian yang digunakan adalah desain penelitian cross sectional. Lokasi penelitian adalah di
kecamatan Indralaya Utara yaitu desa Tanjung Pering, desa Tanjung Baru dan kelurahan
Timbangan. Sampel penelitian ini adalah semua penduduk kelompok usia pra lansia (usia 45
sampai 59 tahun) dan berdomisili tetap di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Kriteria eksklusi sampel
adalah responden sedang minum obat hipertensi atau sedang hamil. Besar sampel yang digunakan
pada penelitian ini sebanyak 150 orang pra lansia. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini
adalah purposive sampling.
Variabel yang diteliti adalah umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, hipertensi
dan obesitas sentral. Variabel hipertensi diukur melalui pengukuran tekanan darah sistolik dan
diastolik responden. Responden dinyatakan hipertensi apabila hasil pengukuran tekanan darah
sistolik ≥140 mmhg dan tekanan darah diastolik ≥90 mmhg. Sedangkan variabel obesitas sentral
diperoleh melalui pengukuran terhadap lingkar perut responden. Responden laki-laki dikategorikan
mengalami obesitas sentral apabila hasil pengukuran lingkar perut ≥ 90 cm sedangkan responden
perempuan dikategorikan mengalami obesitas sentral jika memiliki lingkar perut ≥ 80 cm. Analisa
data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa univariat (deskriptif) dengan penyajian data
menggunakan tabel.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 137
HASIL PENELITIAN
Distribusi frekuensi karakteristik responden dan hasil pengukuran terhadap tekanan darah
kelompok pra lansia (usia 45 sampai 59 tahun) dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik responden (n= 150)
Variabel Total Responden
n %
Variabel Kategorik
Jenis kelamin
Laki-laki 47 31,3
Perempuan 103 68,7
Tingkat pendidikan
Tidak sekolah 16 10,7
SD 72 48 SMP 30 20
SMA 27 18
Perguruan tinggi 5 3,3
Pekerjaan
Tidak bekerja 47 31,3
Petani 35 23,3 Pedagang 30 20
Buruh 10 6,7
PNS 2 1,3
Pegawai swasta 10 6,7 Lainnya 16 10,7
Variabel numerik
Umur
Mean 51,45 Standar deviasi 5,239
Minimum 42
Maksimum 59
Tekanan darah sistolik
Mean 134,42
Standar deviasi 23,171 Minimum 90
Maksimum 200
Tekanan darah diastolik
Mean 89,77
Standar deviasi 13,752
Minimum 60 Maksimum 130
Berdasarkan Tabel 1 diatas, hampir dua per tiga total responden (68,7%) adalah laki-laki.
Mayoritas responden berpendidikan Sekolah dasar (SD) sebanyak 48%, dan mayoritas tidak
bekerja sebanyak 31,3%. Rata-rata responden berusia 51,45 tahun dengan standar deviasi 5,239,
rata-rata memiliki tekanan darah sistolik sebesar 134,42 mmhg dengan standar deviasi 23,171 dan
rata-rata memiliki tekanan darah diastolik sebesar 89,77 dengan standar deviasi 13,752.
Tabel 2. Kejadian hipertensi dan obesitas sentral pada pra lansia
Variabel Total Responden
n %
Variabel
Hipertensi
Ya 51 34
Tidak 99 66
Obesitas Sentral
Ya 110 73,3
Tidak 40 26,7
Total 150 100
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 138
Berdasarkan Tabel 2, hampir sepertiga total responden (34%) mengalami hipertensi.
Berdasarkan status obesitas diketahui bahwa mayoritas responden mengalami obesitas sentral
(73,3%).
Tabel 3. Distribusi frekuensi kejadian hipertensi dan obesitas sentral berdasarkan
karakteristik pra lansia
Variabel Hipertensi Obesitas sentral
Ya Tidak Ya Tidak
n % n % n % n %
Jenis kelamin
Laki-laki 24 51,1 23 48,9 30 63,8 17 36,2
Perempuan 27 26,2 76 73,8 80 77,7 23 22,3
Tingkat
pendidikan
Tidak sekolah 6 37,5 10 62,5 12 75 4 25
SD 22 30,6 50 69,4 52 72,2 20 27,8 SMP 8 26,7 22 73,3 21 70 9 30
SMA 11 40,7 16 59,3 21 77,8 6 22,2
Perguruan tinggi 4 80 1 20 4 80 1 20
Pekerjaan
Tidak bekerja 10 21,3 37 78,7 35 74,5 12 25,5
Petani 15 42,9 20 57,1 22 62,9 13 37,1 Pedagang 8 26,7 22 73,3 25 83,3 5 16,7
Buruh 3 30 7 70 7 70 3 30
PNS 1 50 1 50 2 100 0 0
Pegawai swasta 6 60 4 40 6 60 4 40 Lainnya 8 50 8 50 13 81,3 3 18,8
Total 51 34 99 66 110 73,3 40 26,7
Berdasarkan Tabel 3, mayoritas responden mengalami hipertensi adalah laki-laki (51,1%)
dan mayoritas responden yang mengalami obesitas sentral adalah perempuan (77,7%). Berdasarkan
tingkat pendidikan diperoleh hasil bahwa mayoritas kejadian hipertensi dan obesitas sentral terjadi
pada kelompok pra lansia yang berpendidikan perguruan tinggi (80%). Berdasarkan pekerjaan
diketahui bahwa mayoritas hipertensi terjadi pada kelompok pra lansia yang bekerja sebagai
pegawai swasta (60%) sedangkan kejadian obesitas sentral mayoritas terjadi pada kelompok pra
lansia yang bekerja sebagai PNS (100%).
PEMBAHASAN Hipertensi
Sepertiga dari total responden diketahui mengalami hipertensi (tabel 2). Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa rata-rata tekanan darah sistolik pada responden sebesar 134,42 mmhg dan
rata-rata tekanan dara diastolik sebesar 89,77 mmhg (tabel 1). Mayoritas hipertensi yang terjadi
saat ini sebanyak 90% adalah hipertensi esensial (hipertensi primer) yaitu kejadian hipertensi yang
tidak diketahui penyebabnya.9
Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sebanyak 46%
dari penderita hipertensi tidak mengetahui jika mereka mengalami hipertensi.10
Berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa mayoritas laki-laki mengalami hipertensi (tabel
2). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kelompok pra
lansia laki-laki lebih berisiko mengalami hipertensi dibandingkan perempuan.11
Perempuan lebih
terhindar dari hipertensi dibanding laki-laki karena adanya hormon estrogen pada perempuan.
Hormon estrogen pada perempuan berfungsi dalam meningkatkan kadar high density lipoprotein
(HDL) yang mempengaruhi proses asteroklerosis. Namun pada saat perempuan telah mengalami
menopause maka risiko hipertensi akan meningkat dibandingkan laki-laki.12
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 139
Mayoritas responden yang berpendidikan perguruan tinggi mengalami hipertensi dan hanya
seperempat dari total responden yang berpendidikan SMP menglami hipertensi (tabel 2). Hasil
penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitan sebelumnya dima risiko hipertensi akan
semakin meningkat pada tingkat pendidikan yang rendah.13,14
Pendidikan rendah memiliki
kemungkinan seseorang mengalami hipertensi yang disebabkan kurangnya informasi atau
pengetahuan yang menimbulkan perilaku dan pola hidup yang tidak sehat seperti tidak tahu nya
tentang bahaya, serta pencegahan dalam terjadinya hipertensi.15
Responden dengan pendidikan
tinggi biasanya memiliki pekerjaan tertentu dan hal ini cenderung mempengaruhi aktifitas fisik
mereka. Oleh karena itu, seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi dapat berisiko lebih
besar mengelami hipertensi karena rendahnya aktifitas fisik mereka meskipun pengetahuan
mengenai hipertensi cukup baik dibanding responden yang berpendidikan rendah.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden yang bekerja sebagai pegawai
swasta mengalami hipertensi (tabel 3). Pekerjaan merupakan salah satu faktor risiko terjadinya
hipertensi.10
Hal ini dikarenakan pekerjaan berkaitan dengan tingkat stress seseorang.16
Beban kerja
sebagai pegawai swasta cenderung menimbulkan tingkat stress kerja yang tinggi dikarenakan
tingginya tuntutan dan target dari pekerjaan. Sehingga seseorang yang bekerja sebagai pegawasi
swasta berpeluang menderita hipertensi lebih besar dibanding pekerjaan lain meskpiun aktifitas
fisik mereka cukup baik. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa stress terutama stress
psikososial merupakan faktor risiko terjadinya hipertensi.17
Obesitas sentral
Dua pertiga dari total responden mengalami obesitas sentral (tabel 2). Sebagian besar orang
dengan usia lanjut mengalami obesitas yang mendorong berbagai masalah penyakit degeneratif
seperti penyakit jantung koroner, hipertensi, diabetes melitus, batu empedu, gout (rematik), ginjal,
sirosis hati dan kanker.18
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian obesitas sentral lebih
banyak terjadi pada perempuan dibanding laki-laki (tabel 3). Hasil penelitian ini mendukung
penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa obesitas sentral cenderung lebih banyak pada
perempuan dibandingkan laki-laki.19
Pada wanita, berat badan dipengaruhi oleh beberapa kejadian
seperti kehamilan, kontrasepsi oral dan menopause. Berat badan dan perubahan distribusi lemak
terjadi setelah menopause. Penurunan sekresi estrogen dan progesteron mengubah sel lemak secara
biologis sehingga terjadi peningkatan deposisi lemak sentral.20
Hasil analisis diperoleh bahwa persentase obesitas sentral paling banyak terjadi pada
responden pra lansia yang berpendidikan perguruan tinggi (tabel 3). Hasil penelitian ini
mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ada hubungan yang bermakna secara
statistik antara tingkat pendidikan dan obesitas sentral.21
Semakin tinggi tingkat pendidikan
responden maka semakin tinggi persentase kejadian hipertensi (tabel3). Seseorang dengan tingkat
pendidikan tinggi cenderung memiliki status bekerja. Beberapa pekerjaan berisiko adanya aktifitas
fisik yang rendah sehingga mendorong terjadinya obesitas pada mereka.
Berdasakan pekerjaan diketahui bahwa kejadian obesitas sentral mayoritas terjadi pada
pegawai negeri sipil (tabel 3). Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang
menyatakan ada hubungan antara pekerjaan dan obesitas sentral.22
Sebuah penelitian pada aparatur
sipil negara menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan obesitas sentral adalah asupan
serat, asupan lemak dan aktifitas fisik ringan.23
Seseorang yang bekerja sebagai karyawan
perkantoran berpeluang memiliki aktifitas fisik ringan dan pada akhirnya berujung kepada
terjadinya obesitas sentral. Hal ini dikarenakan selama bekerja mereka cenderung lebih banyak
duduk dan kurang gerak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa seorang pekerja dengan
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 140
aktifias ringan lebih berisiko mengalami obesitas sentral dibandingkan seorang pekerja dengan
aktivitas fisik yang sedang maupun pekerja dengan aktifitas yang berat.24
KESIMPULAN DAN SARAN
Laki-laki pada usia pra lansia lebih banyak menderita hipertensi sedangkan perempuan lebih
banyak yang menderita obesitas sentral. Tingkat pendidikan yang tinggi, status pekerjaan yang
berkaitan dengan aktifitas fisik yang rendah serta tingkat stress yang tinggi dapat meningkatkan
peluang mengalami hipertensi dan obesitas sentral.
Saran dari penelitian ini adalah pentingnya meningkatkan edukasi mengenai faktor risiko
hipertensi dan obesitas sentral kepada kelompok usia pra lansia terutama mereka yang masih aktif
bekerja dengan jenis pekerjaan yang berisiko aktifitas fisik rendah dan tingkat stress yang tinggi.
DAFTAR PUSTAKA
1. Kementerian Kesehatan RI. Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018. Jakarta;
2018.
2. Nuraini B. Risk factors of hypertension. J Major [Internet]. 2015;4(5):10–9. Available from:
http://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/download/602/606
3. WHO. Hypertension [Internet]. 2015. Available from:
http://www.who.int/topics/hypertension/en/
4. Widjaya N, Anwar F, Laura Sabrina R, Rizki Puspadewi R, Wijayanti E. Hubungan Usia
Dengan Kejadian Hipertensi di Kecamatan Kresek dan Tegal Angus, Kabupaten Tangerang.
Yars Med J. 2019;26(3):131.
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Laporan Provinsi Sumatera Selatan
Riskesdas 2018. Jakarta; 2019.
6. Singh S, Shankar R, Singh GP. Prevalence and Associated Risk Factors of Hypertension: A
Cross-Sectional Study in Urban Varanasi. Int J Hypertens. 2017;2017.
7. Jiang SZ, Lu W, Zong XF, Ruan HY, Liu Y. Obesity and hypertension (Review). Exp Ther
Med. 2016;12.
8. Kartika J, Purwaningsih E. Hubungan Obesitas pada Pra Lansia dengan Kejadian Hipertensi
di Kecamatan Senen Jakarta Pusat Tahun 2017-2018. J Kedokt dan Kesehat. 2020;16(1):35.
9. Gunawan L. Hipertensi. Yogyakarta: Penerbit Kanisius; 2007.
10. Widiana IMR, Ani LS. Prevalensi dan karakteristik hipertensi pada pralansia dan lansia di
Dusun Tengah, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis. E-JURNAL Med. 2017;6(8).
11. Amanda D, Martini S. HUBUNGAN KARAKTERISTIK DAN OBESITAS SENTRAL
DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI. J Berk Epidemiol. 2018;6(1).
12. Alifariki LO dkk. Epidemiologi Hipertensi. Penerbit LeutikaPrio; 2019. 21 p.
13. Kharisyanti F, Farapti. STATUS SOSIAL EKONOMI DAN KEJADIAN HIPERTENSI.
Media Kesehat Masy Indones. 2017;13(3).
14. Tiziana Di Chiara, Alessandra Scaglione, Salvatore Corrao CA, Pinto A, Scaglione R.
Association Between Low Education and Higher Global Cardiovascular Risk. J Clin
Hypertens. 2015;17(5).
15. Maulidina F, Harmani N, Suraya I. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian
Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Jati Luhur Bekasi Tahun 2018. ARKESMAS.
2019;4(1).
16. Ikhwan M, PH1 I, Hermanto. Hubungan Faktor Pemicu Hipertensi Dengan Kejadian
Hipertensi. J Kesehat. 2017;10(2).
17. Istiana M, Yeni. The Effect of Psychosocial Stress on the Incidence of Hypertension in
Rural and Urban Communities. Media Kesehat Masy Indones. 2019;15(4).
18. Maryam RS, Ekasari MF, Rosidawati, Jubaedi A, Batubara I. Mengenal usia lanjut dan
perawatannya. Jakarta: Salemba medika; 2008.
19. Pramono DSHLA, Yunir E, Subekti I. Obesity and central obesity in Indonesia: evidence
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 141
from a national health survey. Med J Indones. 2018;
20. Hastuti P. Genetika Obesitas. Yigayakarta: Gadjah Mada University Press; 2019.
21. Puspitasari N. Faktor Kejadian Obesitas Sentral Pada Usia Dewasa. HIGEIA J PUBLIC
Heal Res Dev. 2018;2(2).
22. Sugianti E, Hardinsyah, Afriansyah N. FAKTOR RISIKO OBESITAS SENTRAL PADA
ORANG DEWASA DI DKI JAKARTA: Analisis Lanjut Data RISKESDAS 2007. Gizi
Indonesa. 2009;32(2):103–16.
23. Masri E, Nova M, Sari RK. Faktor Risiko Obesitas Sentral Pada Aparatur Sipil Negara
(Asn) Di Kota Padang. Sci J Farm dan Kesehat. 2019;9(1):53.
24. Sonya Rosa, Lolita Riamawati. Hubungan Asupan Kalsium, Air, dan Aktivitas Fisik dengan
Kejadian Obesitas Sentral pada Pekerja Bagian Perkantoran . Amerta Nutr. 2019;3(1):33–9.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 142
IMPLEMENTASI MODEL ARIMA (AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING
AVERAGE) GUNA PERAMALAN KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE
DI KOTA SEMARANG
Roro Kushartanti,
1 Maulina Latifah,
2
1Program Studi Kesehatan Masyarakat STIKES HAKLI Semarang
2Program Studi Kesehatan Lingkungan STIKES HAKLI Semarang
Jl. Dr Ismangil No. 27 Bongsari Semarang Barat Kota Semarang Jawa Tengah 50148
Corresponding email : [email protected]
IMPLEMENTATION OF THE ARIMA (AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING
AVERAGE) MODEL USING FORECASTING CASE OF Dengue Hemorrhagic Fever
IN THE SEMARANG CITY
ABSTRACT
Forecasting is an activity of predicting something what will happen in the future with a relatively long time,
with calculation analysis techniques carried out with quantitative and qualitative approaches. ARIMA is a
time series forecasting method that does not require a specific data pattern. This aims study is to analyze the
forecasting DHF cases in the Semarang City especially in the Rowosari Community Health Centre working
area. Data used with monthly data of DHF cases in 2016, 2017, and 2019 as many as 36 datas. This
research is a non-reactive (unobstructive) research which doesn’t require a response from the research
subject and the researcher haven’t interact with the research subject. The best ARIMA model for forecasting
is a model that have requirement for parameter significance, white noise and has smallest MAPE (Mean
Absolute Percentage Error) value. The results is show that the best model for predicting the number of
dengue cases in Rowosari Community Health Centre is : ARIMA model (1,1,1) with a MAPE value of
61.37% and significance coefficient 0.009. ARIMA model (1,1,1) is suitable and feasible to be used for
predicting dengue cases. The data period used can be more coherent, as well as data processing and
analysis, apart from using SPSS 23, it can also be done using the help of several other software, such as
Minitab and Eviews.
Keywords : Forecasting, ARIMA, Dengue Hemmorhagic Fever
ABSTRAK
Peramalan merupakan aktivitas memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan
datang dengan waktu yang relatif lama, dengan teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan
pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. ARIMA merupakan salah satu metode peramalan time series yang
tidak mensyaratkan adanya suatu pola data tertentu. Tekait hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis peramalan kasus DBD Kota Semarang secara khusus di wilayah kerja Puskesmas Rowosari.
Data yang digunakan yaitu data bulanan kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Rowosari tahun 2016, 2017,
dan 2019 sebanyak 36 data. Penelitian ini merupakan penelitian non-reaktif (unobstructive) yang tidak
memerlukan respon dari subyek penelitian serta peneliti tidak melakukan interaksi terhadap subyek
penelitian. Model ARIMA terbaik untuk peramalan adalah model yang memenuhi syarat signifikasi
parameter, white noise dan memiliki nilai MAPE (Mean Absolute Percentage Error) yang terkecil. Hasil
analisis menunjukkan model terbaik untuk peramalan jumlah kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas
Rowosari Kota Semarang adalah model ARIMA (1,0,0) dengan nilai MAPE 43,98% serta koefisien
signifikansi sebesar 0,353. Dengan demikian model ARIMA (1,0,0) cocok dan layak digunakan untuk
peramalan kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Rowosari Kota Semarang. Saran yang dapat disampaikan
yaitu periode data yang digunakan dapat lebih banyak dan runtut, serta pengolahan dan analisis data selain
menggunakan bantuan software SPSS 23 juga dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan beberapa
software lainnya yaitu Minitab dan Eviews.
Kata Kunci: Peramalan, ARIMA, Demam Berdarah Dengue
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 143
PENDAHULUAN
ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) merupakan salah satu model
peramalan yang secara penuh mengabaikan variabel independen, merupakan analisis dan
peramalan data runtun waktu (time series). ARIMA dapat digunakan untuk peramalan jangka
pendek, menengah, dan panjang, namun lebih tepat digunakan untuk peramalan jangka pendek.
Model ini terdiri dari tiga langkah dasar yaitu tahap identifikasi, tahap penaksiran dan pengujian,
dan penaksiran diagnostik. ARIMA merupakan penggabungan antara model AR (Autoregressive), I
(Integrated), dan MA (Moving Average).1
Model ARIMA secara umum ditulis dengan (p,d,q) yang berarti model ARIMA terdiri dari
derajat AR (p), derajat pembeda d dan derajat MA (q). Selain memiliki fungsi peramalan secara
kuantitatif berdasarkan deret waktu, juga dapat menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau
kondisi tertentu.2
Kondisi yang digambarkan bersifat umum, yaitu dapat diaplikasikan pada
berbagai fenomena berbeda seiring berjalannya waktu termasuk dalam bidang kesehatan
masyarakat. Salah satu masalah kesehatan masyarakat yang patut menjadi perhatian adalah Demam
Berdarah Dengue.
Penyakit DBD di Kota Semarang merupakan penyakit endemis dan sering menyebabkan
Kejadian Luar Biasa (KLB). Case Fatality Rate (CFR) DBD di Kota Semarang adalah 1,72%
(standar <1%). Urutan Incidence Rate (IR) dari mulai yang terbesar di adalah Kelurahan
Tembalang, Srondol Kulon, Karangrejo, Sampangan, Lamper Lor, Mijen, Brumbungan, Jomblang,
Karangsari, dan Meteseh.3
Melihat perkembangan kasus DBD di Kota Semarang, serta fakta bahwa
Puskesmas Rowosari yang wilayah kerjanya meliputi daerah endemis DBD, belum pernah
dilakukan peramalan kasus DBD. Oleh sebab itu, perlu suatu metode peramalan untuk meramalkan
jumlah kasus DBD pada tahun yang akan datang sebagai langkah preventif untuk mencegah
terjadinya peningkatan kasus DBD. Data pengamatan jumlah kasus DBD dapat dilihat sebagai data
time series. Data tersebut dapat disajikan melalui model ARIMA.
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model terbaik peramalan ARIMA serta
menganalisis hasil peramalan kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Rowosari.
METODE
Penelitian ini merupakan desain studi non-reaktif (unobstructive), yaitu peneliti tidak
melakukan intervensi dan tidak memerlukan respon dari subyek penelitian.4
Data penelitian
menggunakan data sekunder yang merupakan data bulanan jumlah kasus DBD yang tercatat dan
dilaporkan di wilayah kerja Puskesmas Rowosari tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2019. Data
tersebut dianalisis menggunakan model ARIMA guna mendapatkan suatu model untuk
meramalkan jumlah kasus penyakit DBD di masa yang akan datang.
Langkah-langkah analisis data terdiri dari tahap identifikasi model meliputi pemeriksaan
stasioneritas data dan identifikasi model sementara; penaksiran parameter dan pengujian diagnosis
meliputi uji kenormalan residual; uji white noise dan uji signifikansi parameter; serta tahap
penerapan meliputi penerapan hasil peramalan dan evaluasi.5
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 144
Gambar 1. Kerangka Kerja Penelitian
HASIL PENELITIAN
Berikut ini merupakan plot data jumlah kasus penyakit DBD di Puskesmas Rowosari Kota
Semarang tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2019.
Gambar 2. Plot ACF dan PACF dan 36 Data Jumlah Kasus Penyakit DBD di Wilayah Kerja
Puskesmas Rowosari yang Telah Stasioner
Plot data Gambar 2 menunjukkan bahwa pada plot ACF terdapat lag yang signifikan yaitu
pada lag 1 dan lag 2, begitu juga pada plot PACF terdapat lag yang signifikan yaitu pada lag 1 dan
2. Pola ACF dan PACF yang signifikan artinya bahwa data telah stasioner dan dapat ditentukan
model-model tentatif ARIMA.
Tabel. 1 Peramalan data masing-masing model
Bulan (p,d,q)
(1,0,0)
(p,d,q)
(0,0,1)
(p,d,q)
(1,1,1)
Data Peramalan Data Peramalan Data Peramalan
Januari 0 3,38 0 3,38 0 3,38
Februari 4 3,35 4 3,36 4 3,36
Maret 5 3,33 5 3,33 5 3,33 April 3 3,31 3 3,31 3 3,31
Mei 4 3,28 4 3,28 4 3,28
Juni 2 3,26 2 3,26 2 3,26
Juli 2 3,23 2 3,23 2 3,23 Agustus 1 3,21 1 3,21 1 3,21
September 6 3,18 6 0 6 0
Oktober 4 3,16 4 0 4 0
November 6 3,13 6 0 6 0 Desember 4 3,11 4 0 4 0
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 145
Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa masing-masing model memiliki hasil prediksi yang
hampir sama. Dari masing-masing model terdapat beberapa nilai yang hampir mendekati nilai data
observasi, namun terdapat pula perbedaan nilai yang cukup jauh dengan data observasi, sehingga
diperlukan perhitungan selanjutnya untuk mencari model yang paling efisien.
Penentuan model yang paling efisien dilakukan dengan cara mencari dahulu nilai kesalahan
untuk masing-masing model, sehingga dapat ditentukan model mana yang paling baik.
Tabel. 2 Validasi Kebaikan Model
ARIMA
(p,d,q)
Estimasi
Parameter
Nilai-p MAPE Nilai-p
LJung
Box
(1,0,0) 0,353 <0,001 43,98% 0,270
(0,0,1) 0,248 0,014 45,04% 0,018
(1,1,1) 0,106 0,001 61,57% 0,496
Berdasarkan Tabel 2 maka diperoleh model terbaik dengan memenuhi prinsip signifikansi
parameter mendekati 1, kesalahan minimum (nilai MAPE terkecil) dan syarat white noise (nilai-p>
0,05) yaitu model ARIMA (1,0,0).
PEMBAHASAN
Hasil dari penelitian ini yaitu menentukan model ARIMA mana yang lebih cocok untuk
digunakan pada data jumlah kasus penyakit DBD. Dari model yang sudah didapatkan, merupakan
data mentah yang dijadikan sebagai input untuk masing-masing model untuk kemudian data
prediksi tersebut dibandingkan dengan data observasi dengan melakukan uji kebaikan untuk
melihat model mana yang lebih cocok, dan hasilnya merupakan data olahan hasil peramalan jumlah
kasus di masa yang akan datang.6
Hasil uji kebaikan pada masing-masing model memiliki nilai R-square yang mendekati 1
(<1), hal ini menunjukkan model time series dapat menjelaskan variabel jumlah kasus penyakit
DBD secara signifikan dengan melibatkan observasi masa lalu.7
Hal ini sesuai dengan hasil
penelitian lain tentang peramalan jumlah penderita DBD di Kabupaten Jombang Jawa Timur
dengan pendekatan fungsi transfer single input menyatakan bahwa terdapat kesamaan trend hasil
peramalan dengan data aktual sebanyak 75% yaitu dikatakan signifikan atau valid.8
Nilai MAPE (Mean Absolute Percentage Error) atau ukuran kesalahan relatif yang terdapat
pada hasil analisis merupakan angka persentase kesalahan hasil pendugaan/peramalan terhadap
hasil aktual selama periode waktu tertentu.9 Nilai MAPE pada model ARIMA (0,0,1) sebesar
45,04%. Semakin kecil nilai MAPE maka semakin kecil kesalahan hasil pendugaan. Hasil suatu
metode pendugaan mempunyai kemampuan peramalan sangat baik jika nilai MAPE <10% dan
mempunyai kemampuan pendugaan baik jika nilai MAPE 10-20%. Residual pada model ini sudah
bersifat acak. Hal ini dibuktikan dengan indikator Box L-Jung statistik yang memiliki nilai-p >0,05.
Hasil analisis peramalan mengenai jumlah kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Rowosari
Kota Semarang menyatakan bahwa jumlah kasus berkisar 3-4 kasus tiap bulan, dan akan menurun
di bulan September. Hasil ini dimungkinkan karena pada bulan September sudah memasuki musim
kemarau, dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan
sehingga populasi vektor nyamuk Aedes aegypti mulai berkurang.10
Metode Peramalan dengan menggunakan model ARIMA dapat diaplikasikan bagi
Puskesmas guna mencegah terjadinya kenaikan insidensi atau Kejadian Luar Biasa terutama
penyakit menular yang disebabkan oleh vektor.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 146
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian, untuk data prediksi jumlah kasus penyakit DBD dengan
menggunakan model time series ARIMA berdasarkan nilai R-square dan nilai MAPE, model yang
paling baik adalah model (1,0,0). ARIMA memiliki perfomansi yang baik untuk memprediksi
jumlah suatu masalah di masa yang akan datang dengan durasi waktu jangka pendek, sebagai
langkah preventif mencegah penyakit DBD.
Saran bagi Puskesmas Rowosari Kota Semarang dan Dinas Kesehatan Kota Semarang
diharapkan bisa menerapkan metode peramalan atau memberikan pelatihan khusus kepada staf
yang terkait untuk bisa mengetahui prediksi jumlah kasus penyakit DBD di masyarakat guna
mencegah peningkatan insidensi penyakit DBD terutama di musim penghujan dan mencegah
terjadinya KLB (Kejadian Luar Biasa).
Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencoba metode ARIMA dengan
menggunakan software lain selain SPSS dan mengkombinasikan dengan variabel lain yang
mendukung agar tingkat keakuratan hasil peramalan menjadi lebih baik.
DAFTAR PUSTAKA
1. Makridakis spyros. 2013. Metode dan Aplikasi Peramalan. Jakarta : Erlangga.
2. Ali baroroh. 2013. Analisis Multivariat dan Time Series dengan SPSS 21, edisi I. Jakarta : PT
Elex Media Komputindo.
3. Dinas Kesehatan Kota Semarang. 2017. Profil Kesehatan Kota Semarang Tahun 2017.
Semarang : Dinas Kesehatan Kota Semarang.
4. Burhan bungin. 2013. Penelitian Kualitatif. Jakarta : Kencana Perdana Media Grup.
5. R Martinez, 2017. Geographic Information System for Dengue Prevention and Control.
Scientific Working Group. Report on Dengue. 1-5 October 2016. Geneva, Switzerland,
Copyright World Health Organization on behalf of the Special Programme for Research and
Training in Tropical Disease. Diakses di :
http://www.who.int/tdr/publications/publications/swg_dengue_2.htm tanggal 15 Maret 2019.
6. F. N Hadiansyah. 2017. Prediksi Harga Cabai dengan Pemodelan Time Series ARIMA. Ind
Journal on Computing. Vol.2, Issue I, Maret 2017. Pp 71-78.
7. A. Colin, et al. 1995. An R Squared measured of goodness of fit for some common non linear
regressing models.
8. Soediono, Tito D. 2019. Peramalan Jumlah Penderita Demam Berdarah Dengue di Kabupaten
Jombang Jawa Timur Dengan Pendekatan Fungsi Transfer Single Input. Jurnal Matematika,
Statistika, dan Komputasi. Vol.15, No 2, 10-19. http://journal.unhas.ac.id/index.php/jmsk
9. Willmatt J Cort dan Matsuura kenji. 2015. Advantages of the Mean Absolute Error (MAE)
Over the Root Mean Square Error (RMSE) in Assessing Average Model Performance.
Department of Geography. University of Daleware. Newyork, USA.
10. Ika Milasari. 2018. Peramalan Jumlah Penderita Demam Berdarah Menggunakan Model
ARIMA Musiman (Studi Kasus di RSUD Kabupaten Sidoharjo. Skripsi. Jurusan Matematika,
Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Islam Negeri Malang : Malang.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 147
STUDI PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN
(RUMAH SAKIT TIPE C) KABUPATEN SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Haidar Prawira
1, Ariyanto Nugroho
2, Theresia Puspitawati
3
1Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran Lampung
2,3 Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta
Corresponding email : [email protected], [email protected]
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH IMPLEMENTATION STUDY
AT PRAMBANAN REGIONAL GENERAL HOSPITAL
(C TYPE C HOSPITAL) SLEMAN DISTRICT, YOGYAKARTA
ABSTRACT
Hospital is health care institution that provide individual holistic health services: inpatient, outpatient and
emergency service. Type C hospital is hospital that held 24 hours a day continously so the risk of accident is
very high. Occupational Health and Safety (K3KRS) is an effort to create a safe, healthy, hazard -free
workplace and environment pollution, so as to reduce and or be free froom occupational disease and workd
accident hospital. To know how to implement occupational safety and health (K3) at Prambanan Regional
General Hospital (Type C Hospital) Sleman District, Yogyakarta. It was qualitative research with a case
study approach and conducted at Prambanan Regional Hospital Sleman DIstrict, Yogyakarta. involved 6
informants, 2 as key informants and 4 as triangulation informants. Purposive sampling technique sampling.
Prambanan Hospital already has commitment and formation of K3RS . Program units include employee
health care, safety and security, hazardous materials, disaster preparedness, fire safety, medical equipment,
utility systems and staff education. In the implementation of the K3RS team communicates to all workers and
involves each work unit, but there are some obstacles namely lack of human resources, there are evaluation
meetings but not yet carried out regularly, there are still workers who are less aware of the importance of
K3. Prambanan Hospital has been to implement the program of K3 standards in the workplace implemented
by the K3RS team starting from commitment, program plan, implementation and evaluation. The problem
that arises is the lack of human resources, there are evaluation meetings but it has not been carried out
regularly, there are still workers who are unaware of the importance of K3
Keywords: K3 i, K3RS, SMK3RS, Implementation
ABSTRAK
Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit tipe C
merupakan salah satu rumah sakit yang diselenggarakan 24 jam sehari secara terus menerus sehingga resiko
terjadinya kecelakaan sangat tinggi. Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit (K3RS) merupakan
suatu upaya dalam menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari bahaya serta pencemaran
lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari Penyakit Akibat Kerja dan Kecelakaan Kerja di
rumah sakit. Mengetahui bagaimana penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) di Rumah Sakit
Umum Daerah Prambanan (Rumah Sakit Tipe C) Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan di Rumah
Sakit Umum Daerah Prambanan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta melibatkan 6 informan, 2
sebagai informan kunci dan 4 sebagai informan triangulasi. Teknik sampling purposive sampling. RSUD
Prambanan sudah memiliki komitmen dan pembentukan tim K3RS berdasarkan kebijakan NOMOR:
445/088/A/RSUD Prambanan/2015 yang ditandatangani oleh direktur. Unit program yang dimiliki antara lain
pemeliharaan kesehatan karyawan, keselamatan dan keamanan, bahan berbahaya, kesiapsiagaan menghadapi
bencana, pengamanan kebakaran, peralatan medis, sistem utiliti dan pendidikan staf. Dalam pelaksanaan tim
K3RS mengkomunikasikan keseluruh pekerja dan melibatkan setiap unit kerja, namun terdapat beberapa
kendala yaitu kurangnya SDM, ada rapat evaluasi namun belum terlaksana dengan rutin, masih terdapat
pekerja yang kurang sadar pentingnya K3. RSUD Prambanan sudah melaksanakan program penerapan
standar K3 di tempat kerja yang dilaksanakan oleh tim K3RS mulai dari komitmen, rencana program,
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 148
pelasanaan dan evaluasi. Kendala yang muncul yaitu kurangnya SDM, ada rapat evaluasi namun belum
terlaksana dengan rutin, masih terdapat pekerja yang kurang sadar pentingnya K3
Kata Kunci: Penerapan K3, K3RS, SMK3R
PENDAHULUAN
Satu pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 160 pekerja
mengalami sakit akibat kerja. Kerugian akibat kecelakaan kerja mencapai 4% dari GDP (Gross
Domestic Product) suatu negara. Artinya dalam skala industri, kecelakaan dan penyakit akibat
kerja menimbulkan kerugian 4% dari biaya produksi berupa pemborosan terselubung (hidden cost)
yang dapat mengurangi produktivitas yang pada akhirnya dapat mempengaruhi daya saing suatu
Negara 1
(Ramli, 2013) . Kecelakaan kerja juga mengakibatkan dampak sosial yang besar, yaitu
menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban kecelakaan
dan keluarganya. Oleh karena itu, gerakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi
prioritas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kecelakaan kerja di
wilayah Jateng-DIY hingga Mei 2016 mencapai 13.386 kasus, , 222 mengakibatkan kecacatan, dan
225 kematian2 . Kasus kecelakaan kerja di DIY per Februari 2017 sebanyak 383 yang secara
prosentase meningkat 85% dibandingkan tahun sebelumnya terjadi 206 kasus menurut data dari
BPJS Ketenagakerjaan DIY3.
Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit (K3RS) merupakan suatu upaya dalam
menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari bahaya serta pencemaran lingkungan,
sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan
Kerja (KK) di rumah sakit. Rumah sakit dituntut untuk melaksanakan upaya K3 yang dilaksanakan
secara terintegrasi dan menyeluruh sehingga risiko terjadinya penyakit akibat kerja (PAK) dan
kecelakaan akibat kerja (KAK) di rumah sakit dapat dihindari. Sejalan dengan Permenkes No. 66
tahun 2016 disebutkan bahwa setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan K3RS yang terdiri dari
membentuk dan mengembangkan SMK3 RS serta menerapkan standar K3RS. Penelitian ini
bertujuan yntuk melihat penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) di Rumah Sakit
Umum Daerah Prambanan (Rumah Sakit Tipe C) Kabupaten Sleman Daerah Istimewa
Yogyakarta4.
METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan
penelitian meliputi Ahli K3/Tim K3 (ketua dan sekretaris) Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan
Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, petugas pelayanan medis (perawat dan analis
kesehatan) serta petugas pelayanan non medis (petugas tata usaha dan praktikan) . Teknik sampling
purposive sampling
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Manajemen Risiko Keamanan dan Keselamatan Kondisi Darurat dan Bencana
di RSUD Prambanan
a. Manajemen risiko
Manajemen risiko telah dilakukan mulai dari menentukan konteks, kemudian
mengidentifikasi risiko bersama dengan yang bertanggung jawab di setiap unit, kemudian
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 149
menentukan mana yang harus dikendalikan terlebih dahulu, setelah itu dikomunikasikan kepada
seluruh pekerja melalui rapat atau pertemuan- pertemuan yang melibatkan setiap unit dari rumah
sakit.
Edukasi untuk manajemen risiko di K3 sosialisasikan melalui in house training semua
sudah dilakukan, pokoknya semua yang mengakibatkan munculnya mengakibatkan
suatu kecelakaan kerja semuanyakan suruh melaporkan. Nah cuman kan ada contoh-
contoh seperti ya bagaimana untuk bekerja yang aman, seperti itu..‖ (IT1)
b. Keselamatan dan keamanan
Hasil wawancara dengan informan kunci keselamatan dan keamanan telah dilaksanakan
melalui upaya- upaya pengendalian yang telah disediakan untuk untuk meminimalisir potensi yang
muncul agar memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pekerja maupun pengunjung selama
beraktifitas di lingkungan RSUD Prambanan.
―.. banyak program, contoh... yang sering rawan di rumah sakit pasiennya bayi .... kita
ada satpam juga ada monitoring CCTV nya, itu mungkin keselamatan untuk pencurian
ya, meskipun puncuri itu lebih tahu celahnya cuman kita punya untuk antisipasinya..‖
(IT2)
Lokasi, teknis bangunan rumah sakit sesuai dengan fungsi, kenyamanan dan kemudahan
dalam pemberian pelayanan serta pelindungan semua orang serta prasarana rumah sakit harus
memenuhi standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja penyelanggara
rumah sakit 5.
―..dengan pemasangan tanda- tanda misalnya ada tanda larangan- larangan misalnya
lantai licin seperti itu, terus e ada penyiapan dan pemantauan fasilitas keamanan pasien
ada neskol, trali, hendrail, misal yang ada di bangsal- bangsal itu itu lho mas apa untuk
pegangan pasien itu lho..‖ (IK2)
c. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakuka untuk mencegah terjadinya kebakaran
sedangkan pengendalian kebakaran merupakan upaya yang dilakukan untuk memadamkan api
pada saat terjadi kebakaran dan setelahnya.
―sudah ada di beberapa tempat itu sudah ada terdapat alat kebakaran, itu yang gas itu ya,
terus di ruang- ruang perawat dan bangsal itu tersedia helm, itu helm itu terbagai menjadi
beberapa warna..‖ (IT3)
d. Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana
Untuk kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat dan bencana di RSUD prambanan sudah
dibentuk tim HDP (Hospital Disaster Plan)yang dibuat berdasarkan surat keputusan yang
ditandatangani oleh direktur RSUD Prambanan. Tim ini bertugas mengidentifikasi risiko
terjadinya bahaya bencana dari luar maupun dari dalam rumah sakit.
..ada smoke detector jadi ada detektor asap nggeh disetiap ruang seperti aula, di
ruang P2SPK nggeh jadi nanti ketika ada asap kebakaran itu udah ada bunyi alarm jadi
semua alrm itu denger ternyata ada asap nanti mereka sudah siap siaga. Disitu kita niku
mas, memasang tanda awas bencana kebakaran, terus ada larangan dilarang merokok juga..‖
(IK2)
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 150
Penanggulangan bencana adalah upaya berkelanjutan untuk mengurangi dampak bencana
terhadap manusia dan harta benda. Upaya penanggulangan bencana secara garis besar meliputi,
kesiapsiagaan terutama institusi termasuk pelayanan kesehatan untuk melakukan tindakan dan cara-
cara menghadapi bencana dan penanggulangannya5.
―..Kalau bencana internal rumah sakit apa yang muncul dis itu yang dimungkinkan bisa
muncul apa kebakaran apakah ledakan, apakah keracunan, apakah dari ledakan kompor dari
ledakan dari gas atau apa itu ada, ada semacam apa identifikasi. Kemudian juga ada kalau
eksternal itu apa saja itu juga apa gempa bumi, atau longsor, atau gunung merapi itu juga ada
kita indentifikasi, kemudian kalau yang ada di internal ya apa yang paling kumingkinan besar
ada ya itu kita minimalisir, nah itu juga ada semacam apa simulasi juga kalau diinternalkan
juga bagaimana mengidentifikasi apa mengantisipasi apa dan sebagainya, tapi kalau kita
menghadapi eksternal bagaimana kita menggerakan tenaga kita..‖ (IK1)
RSUD Prambanan memiliki upaya- upaya dalam menghadapi bencana dan
penanggulangannya, dengan tujuan meminimalkan dampak terjadinya kejadian akibat kondisi
darurat dan bencana. RSUD Prambanan juga menyiapkan tim tanggap darurat bencana, menyusun
standar prosedur operasional tanggap darurat bencana dan melakukan simulasi- simulasi mengenai
tanggap darurat bencana.
2. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pekerja di RSUD Prambanan
Pemeriksaan kesehatan dilakukan mulai dari calon menjadi pekerja sampai saat bekerja.
Pemeriksaan kesehatan pekerja rutin tahunan baru saja dilakukan pada bulan Juli untuk yang tahun
2018. Pemeriksaan kesehatan yang ditujukan kepada SDM rumah sakit yaitu dengan tujuan
peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan fisik, mental dan sosial yang setinggi- tingginya
bagi pegawai di semua jenis pekerjaan, pencegahan terhadap gangguan kesehatan pekerja yang
disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan bagi pekerja. Informan kunci juga menyatakan
bahwa terdapat pemeriksaan khusus pada pekerja serta pemberian imunisasi4.
Standar pelayanan kesehatan kerja di rumah sakit perlu dilakukan dengan melakukan
pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, melakukan pemeriksaan berkala bagi pekerja di rumah
sakit, pemeriksaan khusus dilakukan kepada SDM rumah sakit yang terdapat dugaan- dugaan
tertentu mengenai gangguan- gangguan kesehatan perlu dilakukan pemeriksaan khusus sesuai
dengan kebutuhan. Pemeriksaan kesehatan khusus diadakan pula apabila keluhan- keluhan diantara
SDM rumah sakit, atau atas pengamatan dari organi pelaksanan K3RS 5.
RSUD Prambanan memiliki program pemeriksaan kesehatan kepada pekerja dmulai dari
pemeriksaan kesehatan sebelum diterima menjadi pekerja atau karyawan di RSUD Prambanan,
pemeriksaan kesehatan rutin tahunan dan pemeriksaan lanjut untuk yang terdiagnosa memiliki
penyakit tertentu. Namun, program ini memiliki kekurangan yakni belum memiliki program
pemeriksaan kesehatan pasca bekerja untuk karyawan yang telah pensiun.
3. Pengelolaan Sarana Prasarana dan Limbah
a. Pengelolaan Prasarana RSUD Prambanan
RSUD Prambanan mengupayakan ketersediaan prasarana sebagai penunjang seperti air,
listrik, jaringan komunikasi, gas medis dan lain- lain agar dapat tetap dapat digunakan selama 24
jam dengan pemberian upaya alternatif jika terdapat kendala pada sumber utama.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 151
..kita selain mengadakan apa namanya mm.. subtitusinya kalau itu gagal jadi kalau ada
listrik ya ada gensetnya, kalau ada air sumur ya ada air PDAMnya, ..Kalau untuk gas medis
ya untuk upaya kita mungkin dulu pasien dikit kita pakai tabung karena kita pelayanan dari
manual kita tingkatkan menjadi sentral..‖ (IT2)
RSUD Prambanan merupakan rumah sakit tipe C Menurut Permenkes Nomor 56 tahun 2014
rumah sakit tipe C menyediakan pelayanan darurat yang artinya disenggarakan 24 jam sehari secara
terus menerus sehingga harus ada pula prasarana nonklinik yang dapat selalu berfungsi untuk
menunjang keberlangsungan pelayanan yang mendasar yaitu perawatan yang aman7. Pengelolaan
prasarana di rumah sakit sudah memiliki prasarana penunjang yang terolah. Menurut Permenkes
Nomor 66 tahun 2016 mengenai pengelolaan prasarana rumah sakit atau sistem utilitas memiliki
sasaran seperti air bersih dan listrik tersedia selama 24 jam, rumah sakit mengidentifikasi area dan
layanan yang memiliki kontaminasi atau gangguan listrik dan air, penyediaan sumber- sumber
alternatif dalam keadaan darurat. Tata udara, gas medis, sistim kunci, sistim perpipaan limbah
berfungsi dengan ketentuan4..
Kegiatan dalam pengelolaan prasarana mulai dari invetarisasi dan melibatkan pihak ke tiga
jika terdapat perbaikan yang tidak mampu dikerjakan oleh petugas. Kendala dalam pengelolaan
prasarana yaitu kurangnya sumbaya manusia dalam pengelolaan prasarana.
b. Pengelolaan Peralatan Medis
Pengelolaan peralatan medis, terdapat pemeliharaan rutin yang dilakukan IPSRS maupun
pihak ke tiga dalam hal perbaikan. Kalibrasi juga dilakukan untuk kepentingan ketepatan
penghitungan ataupun yang lain mengenai alat medis.
―..pemeliharaanya itu juga di IPSRS. Nanti ya kita di IGD kita hanya
menyimpan di tempat yang disediakan, kalau ada kerusakan nanti kita telfon
bagian yang bersangkutan, seperti itu‖ (IT1)
Peralatan medis merupakan sarana pelayanan di rumah sakit dalam meberikan tindakan
kepada pasien baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengelolaan peralatan medis dari
aspek keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya memastikan sistem peralatan medis aman
dan dapat melindungi bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasein maupun pengunjung4.
c. Pengelolaan Bahan berbahaya dan Beracun (B3)
Prinsip dasar pencegahan dan pengendalian B3 yaitu dimulai dari identifikasi semua B3 dan
instalasi yang akan ditangani untuk mengenal ciri- ciri dan karakteristik, sumber informasi
didapatkan dari MSDS, setelah itu evaluasi, pengendalian sebagai alternatif, seperti melakukan
administrasi, pemasangan label7. Untuk mengurangi risiko karena penangan bahan berbahaya
yaitu salah satunya dengan upaya subtitusi atau mengganti penggunaan bahan berbahaya dengan
bahan yang kurang berbahaya.
―..kita kumpulkan kan kita ada anu ya tempat sampah yang kita pilahkan sampah medis,
sampah- pah non medis. Sampah medis kita anukan sendiri dengan plastik warna kalau gak
salah kuning atau apa itu, kemudian dari itu kita tutup kita kumpulkan kita simpan di TPS,
setelah di TPS itu kita bekerja sama dengan pihak ketiga karena untuk pemusnahan sampah
mediskan harus ada tata cara sendiri..‖ (IK1)
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 152
Limbah medis atau sampah medis rumah sakit termasuk kedalam kategori limbah berbahaya
dan beracun yang sangat penting untuk dikelola secara benar. Sebagian limbah medis termasuk
kedalam kategori limbah berbahaya dan beracun sebagian lagi termasuk kedalam kategori infeksius
6.
Penanganan keadaan darutan bahan berbahaya dan beracun (B3) yaitu dengan melakukan
pelatihan dan simulasi tumpahan bahan berbahaya dan beracun (B3), menerapkan prosedur untuk
mengelola tumpahan dan paparan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta menerapkan mekanisme
pelaporan dan penyelidikan (Investigasi) untuk tumpahan dan paparan bahan berbahaya dan
beracun (B3)4.
4. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah sakit (SMK3RS)
RSUD Prambanan sudah memilki komitmen mengenai K3 ditunjukan dengan pembentukan
tim K3 di RSUD Prambanan yang sudah di tanda tangani oleh Direktur RSUD Pambanan.
Perencanaan program dibuat kemudian baru di komunikasikan kepada seluruh karyawan yang ada
di RSUD Prambanan, kemudian dalam pelakasanaan program berproses dan dilakukan monitoring
untuk perbaikan kedepanya. Evaluasi pelaksanaan dalam bentuk rapat tim K3 belum dilaksanakan
dengan rutin, rapat evaluasi dilaksanakan jika hanya temuan- temuan permasalahan dalam
pelaksanaan.
SMK3 harus ada di rumah sakit karena rumah sakit memiliki potensi bahaya yang besar
seperti, penyebaran penyakit, bahan- bahan kimia yang berbahaya, kecelakaan akibat kerja dan
lain- lain. Menururt Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3, setiap
tempat kerja wajib menerapkan SMK3 di perusahaan yang mempekerjakan lebih dari atau sama
dengan 100 orang atau mempunyai potensi bahaya yang tinggi9. Pengupayaan komunikasi yang
telah dilaksanakan dari tim K3 melalui in house training,
untuk melaksanakan pelaksanakan dengan maksimal memiliki hambatan ―iya. untuk
menjalankan K3 ini ya kendalanya sebenarnya e.. kesadaran dari kita si, jadi kita
misalnya memprogramkan kita jadi kadang ada yang belum tahu, jadi sudah kita
sarankan menggunakan ini, mrnggunakan alat proteksi diri dan sebagainya, kadang kala
ada yang merasa itu belum e.. belum ada yang merasa gak perlu itu sebagainya..‖ (IK1)
Kendala yang terjadi adalah kesadaran karyawan yang merasa tidak perlu dalam penggunaan
alat yang berfungsi melindungi diri dalam melaksanakan pekerja, kemudian masih terdapat
karyawan yang belum memahami mengenai K3 walaupun sudah disampaikan melalui in house
training ataupun rapat, masih terdapat karyawan yang kurang menyadari penting nya K3 dalam
kerja ataupun kurangnya pemhaman mengenai kebijakan ataupun komitmen yang telah diterapkan
di rumah sakit.
Rumah sakit merupakan tempat kerja yaang memilki dampak negatif terhadap timbulnya
penyakit dan kecelakaan akibat kerja 4. Oleh sebab itu rumah sakit perlu melaksanakan prosedur 1)
embuat kebijkan tertulis dari pemimpin rumah sakit; 2) menyediakan organisasi K3RS; 3)
melakukan sosialisasi K3RS pada seluruh jajaran ; 4) membudayakan perilaku K3; 4)
meningkatkan SDM yang profesional dalam bidang K3 di masing- masing unit; 5) meningkatkan
sistem informasi analisis.
RSUD Prambanan sudah memiliki komitmen melaksanakan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit (SMK3RS) yang ditunjukkan dengan kebijakan
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 153
dan pembentukan tim penanggu jawab K3, pembuatan program, pelaksanaan program, evaluasi dan
peningkatan program.. Evaluasi dilakukan dalam rapat pembahasan, namun belum ada rapat rutin
yang dilakukan untuk melakukan penentuan peningkatan program.
KESIMPULAN
RSUD Prambanan sudah memilki komitmen terhadap K3 melalui kebijakan dan
pembentukan tim penanggung jawab K3, memiliki program K3, pelaksaan program K3 yang terus
di monitoring dan perbaikan. Penerapan manajemen risiko yang ada di RSUD Prambanan
dilakukan bersama- sama untuk mengidentifikasi risiko bahaya dan melakukan pemantauan,
perbaikan secara berkala.
Pemeriksaan kesehatan pekerja yang telah dilaksanakan yaitu mulai dari pemeriksaan
kesehatan sebelum diterima menjadi pekerja, pemeriksaan kesehatan rutin tahunan, imunisasi, dan
pemeriksaan lanjutan untuk pekerja yang terdiagnosis penyakit tertentu. Pemeriksaan pasca bekerja
untuk pekerja yang sudah pensiun belum terlaksana di RSUD Prambanan.
Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) telah terlaksana sesuai standar dengan
melibatkan pihak terkait untuk melakukan identifikasi, menyiakan dan memiliki MSDS, pembuatan
tandar prosedur operasional (SPO) dan penanganan keadaan darurat B3.
Kegiatan dalam pengelolaan prasarana mulai dari invetarisasi dan melibatkan pihak ketiga
jika terdapat perbaikan yang tidak mampu dikerjakan oleh petugas. Pengecekan dan pengaktifan
sumber alternatif termasuk dalam program, Kendala dalam pengelolaan prasarana yaitu kurangnya
sumbaya manusia dalam pengelolaan prasarana.
Pemeliharaan peralatan medis seperti sterilisasi dilaksanakan oleh pekerja yang bersangkutan
seperti perawat, bidan, analis. Sedangkan yang bersifat detail seperti pengecekan dan perbaikan
dilaksanakan oleh karyawan pada bagian teknisi yaitu Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit (IPSRS).
Tim K3 sudah melakukan penyusunan pedoman tanggap darurat bencana, membentuk tim
tanggap darurat bencana, menyusun standar prosedur operasional tanggap darurat bencana dan
melakukan simulasi- simulasi mengenai tanggap darurat bencana
ETIKA PENELITIAN
Penelitian ini telah mendapat persetujuan ethical clearence dari komisi etik UNRIYO
khususnya Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat dengan No. 174.1/UNRIYO/PL/VII/2018
DAFTAR PUSTAKA
1. Ramli, S. Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektiff K3 OHS Risk Management.
Jakarta: Dian Rakyat 2013
2. Iswahyudi.(2016). .Kecelakaan Kerja Tinggi, 21 RS kembangkan Trauma Center.
http://jateng.metrotvnews.com, diperoleh pada 08 Desember 2017
3. Kementerian Kesehatan Reublik Indonesi. (2016). Permenkes Nomor 66 Tahun2016 Tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit. Jakarta: Menteri Kesehatan
4. BPJS Ketenagakerjaan Indonesia. (2016). Internet. Jumlah Kecelakaan Kerja Di Indonesia
Masih Tinggi. http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/ 5769/jumlah-kecelakaan-di-
Indonesiamasih-tinggi.html, diperoleh pada 08 Desember 2017
5. Wiarto. Tanggap Darurat Bencana Alam. Surakarta: Gosyen Publising 2017
6. Sucipto. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yogyakarta: Gosyen Publishing 2014
7. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). Permenkes Nomor 56 Tahun 2014
Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Jakarta: Menteri Kesehatan
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 154
8. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2010). Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor:1087/MENKES/SK/VIII/2010 Tentang Standar Keselamatan Kerja di
Rumah Sakit. Jakarta: Menteri Kesehatan
9. Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang Sistem
Menejemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: Kementrian Sekretariatan Republik
Indonesia
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 155
PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) DI PRAKTIK MANDIRI BIDAN
PADA PERTOLONGAN PERSALINAN
Sugiharti, Heny Lestary, Eva Laelasari Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan
Jl. Percetakan Negara No. 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Corresponding email : [email protected]
THE USE OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) AMONG INDEPENDENT
MIDWIVERY PRACTICE IN ASSISTING CHILDBIRTH
ABSTRACT
Childbirth is an activity carried out by midwives who are at high risk of being infected with HIV and
hepatitis viruses due to exposure to various patient body fluids, such as blood and amniotic fluid. The use of
personal protective equipment (PPE) can protect the skin and mucous membranes from the risk of exposure
to blood, body fluids, secretions, excreta, non-intact skin and mucous membranes from patient to midwives
and vice versa. This study aimed to describe the use of personal protective equipment among independent
midwifery practice in assisting childbirth. The research design was cross sectional with quantitative and
qualitative methods. The sample of the study was 38 midwives who had worked for at least 3 years in the
midwife's independent practice who became the research analysis unit. Meanwhile, for qualitative in-depth
interviews were conducted with midwives and program officers at the health office. Quantitative results
showed that the PPE used by midwives according to midwives in assisting childbirth were aprons (100%),
gloves (92.1%) and masks (63.2%), and only 18,4% of midwives use PPE in assisting childbirth. It also
found from the qualitative results the reason of not using PPE such as goggles and boots. Most of midwives
experiencing vision disturbance when using googles and difficulty of walking because of wearing heavy and
slippery boots. The PPE most often used by midviwes in assisting childbirth is an apron, gloves and
masks, and most midwives do not use PPE completely to help deliveries. While the reasons for not
using PPE, most of the midwives stated that the use of protective glasses disturbed their eyesight
and that the use of boots was quite heavy and slippery.
Key words : Personal Protective Equipment, midwife, childbirth
ABSTRAK
Persalinan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bidan berisiko tinggi terinfeksi virus HIV dan hepatitis
karena berhubungan dengan cairan tubuh pasien seperti darah dan air ketuban. Penggunaan Alat Pelindung
Diri (APD) dapat melindungi kulit dan membran mukosa dari risiko terpajan darah, cairan tubuh, sekret,
ekskreta, kulit yang tidak utuh dan selaput lendir dari pasien ke tenaga kesehatan dan sebaliknya. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pemanfaatan alat pelindung diri di praktik mandiri bidan dalam
menolong persalinan. Disain penelitian adalah potong lintang, dengan metode kuantitatif dan kualitatif.
Sampel penelitian adalah 38 orang bidan yang sudah bekerja minimal 3 tahun di praktik mandiri bidan yang
menjadi unit analisis penelitian. Sedangkan untuk kualitatif dilakukan wawancara mendalam dengan bidan,
dan penanggungjawab program di Dinas Kesehatan.Dari hasil kuantitatif menunjukkan bahwa APD yang
digunakan oleh bidan menurut jawaban bidan dalam menolong persalinan adalah apron (100%), sarung
tangan (92,1%) dan masker (63,2%), serta hanya 18,4% bidan yang menggunakan APD secara lengkap
dalam menolong persalinan. Hasil kualitatif didapatkan alasan tidak menggunakan APD, yaitu sebagian besar
bidan menyatakan penggunaan kacamata pelindung mengganggu penglihatan dan penggunaan sepatu boots
berat dan licin. APD yang paling sering digunakan oleh bidan dalam menolong persalinan adalah apron,
sarung tangan dan masker, dan sebagian besar bidan tidak menggunakan APD secara lengkap dalam
menolong persalinan. Sedangkan alasan tidak menggunakan APD, sebagian besar bidan menyatakan bahwa
penggunaan kacamata pelindung mengganggu penglihatan dan penggunaan sepatu boots cukup berat dan
licin.
Kata kunci : Alat Pelindung Diri, bidan, persalinan
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 156
PENDAHULUAN
Kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan
pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan,
pasca persalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan
reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan wewenangnya1 Persalinan
merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bidan, berisiko tinggi terinfeksi virus HIV dan hepatitis
karena berhubungan dengan cairan tubuh pasien seperti darah dan air ketuban2. Risiko penularan
biasanya terjadi karena kecelakaan akibat tertusuk jarum suntik bekas pakai secara tidak sengaja,
pisau bedah, darah atau cairan lain pasien yang terkena luka terbuka tenaga kesehatan 3.
Pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan bertujuan untuk
melindungi pasien, tenaga kesehatan, pengunjung yang menerima pelayanan kesehatan serta
masyarakat dalam lingkungannya dengan cara memutus siklus penularan penyakit infeksi melalui
kewaspadaan standar. Kewaspadaan standar adalah kewaspadaan yang diterapkan secara rutin
dalam perawatan seluruh pasien di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, baik yang
telah didiagnosis, diduga terinfeksi atau kolonisasi. Alat Pelindung Diri adalah salah satu
komponen utama dari 11 komponen utama yang harus dilaksanakan dan dipatuhi dalam
kewaspadaan standar 4.
Berdasarkan Permenkes RI No 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan
Pengendalian Infeksi (PPI) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, alat pelindung diri adalah pakaian
khusus atau peralatan yang di pakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisik, kimia,
biologi/bahan infeksius. APD terdiri dari sarung tangan, masker/Respirator Partikulat, pelindung
mata (goggle), perisai/pelindung wajah, kap penutup kepala, gaun pelindung/apron, sandal/sepatu
tertutup (Sepatu Boot). Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28 Tahun 2017 Tentang Izin
dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, menyebutkan daftar peralatan praktik bidan yang harus
tersedia antara lain adalah apron atau celemek, kacamata pelindung, sepatu boots, tutup kepala,
sarung tangan, dan masker5. Penggunaan Alat pelindung Diri (APD) dapat melindungi kulit dan
membran mukosa dari resiko pajanan darah, cairan tubuh, sekret, ekskreta, kulit yang tidak utuh
dan selaput lendir dari pasien ke petugas dan sebaliknya 4. APD adalah suatu alat yang mempunyai
kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh
dari potensi bahaya di tempat kerja 6.
Sebanyak 35 juta petugas kesehatan di seluruh dunia setiap tahun diperkirakan 3 juta petugas
kesehatan terinfeksi penyakit melalui darah, dengan rincian 2 juta terinfeksi Hepatitis B, 900.000
terinfeksi Hepatitis C dan 170.000 terinfeksi HIV. Di negara berkembang lebih dari 90% petugas
kesehatan terinfeksi penyakit 7. Hasil penelitian di Puskesmas Tasikmalaya (2008), sebanyak 31%
perawat tertusuk jarum suntik, 18% perawat tergores pecahan ampul/vial obat dan 51% perawat
terkena cipratan darah/cairan tubuh pasien 8. Sedangkan hasil penelitian Djauhari di Kabupaten
Mojokerto 52,7% bidan desa mengalami luka tusuk jarum suntik 9.
Penelitian Supiana, dkk (2015) di RS PKU Muhamadyah Yogyakarta menunjukkan bahwa
pelaksanaan penggunaan APD di ruang bersalin dan nifas masih belum terlaksana dengan baik 10
.
Sedangkan hasil penelitian Yuliana, dkk (2016) di Kabupaten Bondowoso, bidan menggunakan
APD secara lengkap pada kala I hanya 2,8%, pada kala II dan kala III hanya 11,1% dan semua
bidan tidak menggunakan APD secara lengkap pada kala IV 11
.
Bidan merupakan tenaga kesehatan yang paling berperan (87,8%) dalam memberikan
pelayanan kesehatan ibu hamil dan fasilitas kesehatan yang paling banyak dimanfaatkan ibu hamil
adalah praktik bidan 52,5%. Berdasarkan permasalahan tersebut, pada tahun 2016 dilakukan
penelitian dengan tujuan untuk mengetahui gambaran penggunaan alat pelindung diri di Praktik
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 157
Mandiri Bidan dalam menolong persalinan di Jawa Barat dan Kalimantan Timur. Hal ini penting
untuk mengantisipasi meningkatnya risiko tertularnya bidan pada saat menolong persalinan ibu
yang terinfeksi virus hepatitis ataupun HIV-AIDS, terutama di wilayah Jawa Barat dan Kalimantan
Timur yang merupakan provinsi dengan proporsi pemanfaatan bidan dalam pemeriksaan kehamilan
dan persalinan paling tinggi 12
.
METODE
Penelitian dilakukan pada tahun 2016, dengan lokasi penelitian dilakukan di kabupaten
terpilih di Jawa Barat dan Kalimantan Timur. Disain penelitian adalah cross sectional, dengan
metode kuantitatif dan kualitatif. Populasi penelitian ini adalah Praktik Mandiri Bidan (PMB) di
kabupaten/kota terpilih dan ibu yang pernah menjadi pasien persalinan di PMB yang menjadi unit
analisis penelitian tersebut.
Sampel adalah PMB yang dipilih berdasarkan lama beroperasi, yaitu minimal selama 3 tahun
dengan berdasarkan jumlah sampel minimal, yaitu 38 bidan. Pengambilan sampel dilakukan
dengan cara sampling purposive. Untuk kuantitatif dilakukan wawancara terstruktur dengan
menggunakan kuesioner sedangkan untuk kualitatif dilakukan wawancara mendalam dengan bidan,
dan penanggungjawab program di Dinas Kesehatan.
HASIL PENELITIAN Hasil Kuantitatif
Hasil yang disajikan pada penelitian ini dibagi menjadi hasil kuantitatif dan kualitatif. Hasil
kuantitatif ditampilkan pada tabel 1 sampai dengan tabel 4 seperti di bawah ini. Sedangkan hasil
kualitatif disajikan dalam bentuk kutipan hasil wawancara mendalam dengan para informan.
Tabel 1. Penggunaan Alat Pelindung Diri Bidan Pada Pertolongan Persalinan
Jenis APD N Ya %
Apron 38 38 100,0
Sarung tangan 38 35 92,1
Sepatu boots 38 24 63,2
Masker 38 24 63,2 Kacamata pelindung 38 11 28,9
Tutup kepala 38 7 18,4
Tabel 1 di atas menunjukkan APD yang digunakan oleh bidan pada saat menolong
persalinan. Penggunaan APD yang paling banyak digunakan bidan pada saat menolong persalinan
adalah apron (100%) dan yang paling sedikit digunakan adalah tutup kepala (18,4%). Bidan yang
menggunakan kacamata pelindung juga masih sedikit (28,9%), demikian juga untuk sepatu boots
dan masker (masing – masing hanya 63,2%).
Tabel 2. Penggunaan Alat Pelindung Diri Yang Lengkap Pada Bidan Dalam Pertolongan
Persalinan
Kelengkapan APD N Ya %
Lengkap 38 7 18,4
Tidak Lengkap 38 31 81,6
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 158
Tabel 2 menunjukkan penggunaan APD yang lengkap pada bidan dalam menolong
persalinan. Penggunaan APD yang lengkap dalam hal ini adalah bidan menggunakan semua APD
dalam menolong persalinan. Dari 38 bidan, hanya 7 bidan saja yang lengkap menggunakan APD
dalam menolong persalinan (18,4%).
Tabel 3. Penggunaan Alat Pelindung Diri Yang Lengkap Pada Bidan Dalam Pertolongan
Persalinan Berdasarkan Karakteristik Bidan
Karakteristik
Kelengkapan APD
Ya Tidak
n % n %
Umur
≥ 35 tahun 7 21,2 26 78,8
< 35 tahun 0 0,0 5 100,0 Pendidikan
D4 Kebidanan 2 18,2 9 81,8
D3 Kebidanan 5 18,5 11 81,5
Lama Bekerja ≥10 Tahun 6 18,8 26 81,2
< 10 Tahun 1 16,7 5 83,3
Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa karakteristik bidan baik umur, pendidikan dan lama bekerja
mayoritas tidak menggunakan APD secara lengkap. Pada bidan yang berumur ≥ 35 tahun ataupun
bidan < 35 tahun keduanya tidak menggunakan APD secara lengkap (78,8% vs 100%). Secara
pendidikan, baik bidan yang berpendidikan D4 kebidanan ataupun D3 kebidanan, mayoritas tidak
menggunakan APD yang lengkap (81,8% vs 81,5%). Demikian juga halnya dengan lama bekerja,
baik bidan yang sudah bekerja ≥ 10 tahun maupun < 10 tahun, mayoritas sama – sama tidak
menggunakan APD yang lengkap (81,2% vs 83,3%).
Tabel 4. Ketersediaan Alat Pelindung Diri Di Ruang Persalinan Pada Praktik Mandiri
Bidan
Jenis APD N Tersedia %
Apron 38 35 92,1
Sarung tangan 38 37 97,4
Sepatu boots 38 24 63,2 Masker 38 31 81,6
Kacamata pelindung 38 26 68,4
Tutup kepala 38 14 36,8
Pada tabel 4 dapat dilihat ketersediaan APD menurut jawaban bidan, yang terdapat di ruang
persalinan Praktik Mandiri Bidan yang menjadi sampel penelitian. APD yang paling banyak
tersedia menurut jawaban bidan adalah sarung tangan dari 38 bidan yang menjawab tersedia ada 35
bidan (97,4%), dan yang paling sedikit tersedia adalah tutup kepala dari 38 bidan yang menjawab
tersedia ada 14 bidan (36,8%). Secara berturut-turut, ketersediaan APD di ruang persalinan Praktik
Mandiri Bidan yang menjadi sampel adalah sebagai berikut : apron (92,1%), masker (81,6%),
kacamata pelindung (68,4%), dan sepatu boots (63,2%).
Hasil Kualitatif
Selain melakukan pengumpulan data kuantitatif terhadap responden bidan, juga dilakukan
pengumpulan data kualitatif terhadap responden bidan, ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 159
Penanggungjawab program Dinas Kesehatan Kabupaten. Berikut adalah gambaran penggunaan
APD di Praktik Mandiri Bidan.
Berdasarkan hasil kualitatif, untuk penggunaan APD sebagian besar bidan pada saat
menolong persalinan tidak menggunakan lengkap. Di Provinsi Kalimantan Timur dalam menolong
persalinan sebagian besar bidan menggunakan apron, sarung tangan dan masker. Sedangkan di
Provinsi Jawa Barat sebagian besar bidan juga menggunakan apron, sarung tangan dan masker.
Sebagian besar bidan jarang menggunakan tutup kepala, kacamata pelindung dan sepatu boots.
―Apron dan sarung tangan selalu dipakai di ruang bersalin.‖ (Bidan di Kabupaten Kutai
Kartanegara)
―Tiba-tiba dateng sudah bukaan lengkap, kita harus jaga diri. cuci tangan dulu, sarung
tangan lalu pake celemek.‖(Bidan di Kota Samarinda)
―Kalo sudah pembukaan lengkap, kita harus sehati-hati mungkin, semua cairan semua pake
sarung tangan. Kalo pembukaan lengkap pastinya apron, masker dan sarung tangan. Ke
asisten kasih tahu bahwa darah itu semua infeksi.‖(Bidan di Kota Bandung)
Adapun kendala dalam penggunaan APD beberapa bidan mengatakan bahwa sepatu boots
jika digunakan berat dan licin. Untuk kacamata beberapa bidan mengatakan penggunaan kacamata
ketika menolong persalinan mengganggu penglihatan karena kacamata sering turun dan buram.
Beberapa bidan juga mengatakan tidak sempat menggunakan APD lengkap karena pasien sudah
akan melahirkan, yang bisa digunakan hanya sarung tangan.
―Kendala kalo tiba-tiba sudah pembukaan lengkap bingung, biasanya sarung tangan. Yang
kendala tidak dipake kacamata google tidak jelas karena mata sudah plus. Boots juga berat
dan licin. Topi juga jarang. Yang sering dipakai celemek, sarung tangan.‖(Bidan di
Kabupaten Kutai Kartanegara)
―Kalo kacamata dan sepatu gak dipake, sepatu gak enak dipake biasanya pake sendal
tertutup yang agak ringan. Kacamata gak terbiasa karena ngga nyaman. Yang sering dipake
celemek, masker dan sarung tangan.‖(Bidan di Kabupaten Karawang)
Berdasarkan hasil kualitatif Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengenai monitoring dan
evaluasi khusus Pengendalian Pencegahan Infeksi di PMB yang di dalamnya termasuk ketersediaan
APD, sebagian besar mengatakan belum ada secara khusus. Kunjungan ke PMB hanya dilakukan
oleh seksi regulasi dinas kesehatan kabupaten/kota untuk penerbitan Surat Ijin Praktek Bidan
(SIPB). Pengawasan pun dilakukan jika ada laporan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) atau
masyarakat mengenai pengelolaan limbah rumah sakit atau klinik mandiri termasuk PMB.
―Belum ada monev khusus, kecuali kunjungan untuk penerbitan atau memperpanjang SIPB‖
(Dinas Kesehatan Kota Bandung)
―Belum ada monev khusus ke PMB. Pengawasan saja dari Dinkes berdasarkan laporan dari
BLH atau masyarakat mengenai pengelolaan limbah RS dan praktik nakes‖ (Dinas
Kesehatan Kota Samarinda)
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 160
PEMBAHASAN
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan dengan
menerapkan kewaspadaan standar. Alat Pelindung Diri adalah salah satu komponen utama dalam
kewaspadaan standar. Pengawasan ketersediaan APD menjadi sangat penting, karena penggunaan
APD untuk mencegah terjadinya transmisi silang dari pasien ke tenaga kesehatan atau sebaliknya.
Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dapat melindungi kulit dan membran mukosa dari
resiko pajanan darah, cairan tubuh, sekret, ekskreta, kulit yang tidak utuh dan selaput lendir dari
pasien ke petugas dan sebaliknya 4. Dalam hal penggunaan APD sebagian besar bidan baik di
Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Jawa Barat tidak menggunakan APD secara lengkap. Hal
ini sesuai dengan penelitian Supiana (2015) bahwa kepatuhan penggunaan APD di ruang bersalin
rendah 10
. Hal ini tidak sesuai dengan Permenkes No 27 tahun 2017, bahwa penerapan
kewaspadaan standar dimana di dalamnya terdapat 11 komponen utama salah satunya adalah
penggunaan APD, komponen utama tersebut semuanya harus dilaksanakan dan dipatuhi. Dalam
melaksanakan Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI), Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik,
Praktik Mandiri wajib menerapkan seluruh program PPI. Dimana salah satu kegiatan PPI yang
harus dilaksanakan adalah kewaspadaan standar 4.
Dari hasil kuantitatif dan kualitatif APD yang paling sering digunakan adalah apron, sarung
tangan dan masker. Hal ini sesuai dengan penelitian Musthafa (2016) bahwa APD yang paling
banyak digunakan petugas kesehatan ketika menolong persalinan adalah sarung tangan (96,8%),
masker (83,9%) dan apron (64,5%) 13
. Sarung tangan adalah APD yang paling sering digunakan
oleh petugas kesehatan. Menurut Departemen Kesehatan RI (2010) sarung tangan wajib digunakan
petugas kesehatan pada saat melakukan tindakan yang kontak atau diperkirakan akan terjadi kontak
dengan darah, cairan tubuh, sekret, eksreta, kulit yang tidak utuh, selaput lendir pasien dan benda
yang terkontaminasi 14
.
Meskipun pedoman pengendalian dan pencegahan infeksi telah diatur, namun penerapan
oleh tenaga kesehatan masih dirasa kurang, salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman
mengenai kewaspadaan universal. Dari hasil penelitian terhadap perawat di salah satu RS di
Kalimantan Selatan menunjukkan hasil bahwa sebanyak 66,7% responden mempunyai pemahaman
yang kurang terhadap penatalaksanaan kewaspadaan universal dan sebanyak 85% responden
memberlakukan kewaspadaan universal hanya diperuntukkan bagi pasien yang menderita
HIV/AIDS 15
. Pemahaman bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan perlu ditingkatkan melalui
sosialisasi maupun pelatihan untuk mencegah terjadinya penularan infeksi penyakit.
Sebagian besar responden penelitian ini juga menyatakan tidak nyaman dalam penggunaan
APD bila harus digunakan secara lengkap. Demikian juga dengan penelitian Yuliana (2016), bahwa
bidan merasa kurang nyaman dalam penggunaan APD secara lengkap pada saat menolong
persalinan. Hal ini dikarenakan bidan merasa tidak nyaman dan malas, serta mengganggap
pemakaian APD mengganggu dan tidak leluasa bergerak yaitu salah satunya sepatu boot 11
.
Menurut Shofia (2016), sebagian bidan di tempat praktik bidan menyatakan bahwa kurang nyaman
dalam penggunaan APD, takut pasien tersinggung dan keterbatasan waktu dalam memakai APD
merupakan alasan bidan tidak menggunakan APD 19
. Berdasarkan hasil penelitian Musthafa (2016),
petugas kesehatan merasa kacamata/glasses tidak dianggap perlu saat akan menolong persalinan,
karena dengan menggunakan kacamata/glasses hanya akan membuat pandangan menjadi kabur.
Sedangkan untuk sepatu boot, sebagian besar petugas kesehatan menggunakan sandal karet selama
menolong persalinan. Menurut petugas kesehatan sepatu boots tidak nyaman dan sulit pada saat
berjalan 13
. Demikian juga dengan penelitian Istiqamah (2019), bahwa bidan dalam pertolongan
persalinan lebih nyaman menggunakan kacamata plus atau minus biasa dan lebih nyaman
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 161
menggunakan sandal jepit dan sandal karet biasa. Sementara untuk penutup kepala sebagian besar
bidan hanya menggunakan jilbab pada saat menolong persalinan16
Alasan ketidaknyaman dalam menggunakan APD selama melakukan kontak dengan pasien
berdeda-beda bagi setiap bidan. Dengan menggali lebih lanjut penyebab ketidaknyamanan tersebut,
diharapkan APD yang dipersyaratkan bagi bidan bisa lebih nyaman digunakan demi keselamatan
bidan. Sebuah penelitian di Jepang mengenai pemilihan sarung tangan dan keluhan dermatitis yang
melibatkan 835 responden bidan, memberikan hasil berikut: sebanyak 30% responden
menggunakan sarung tangan hanya ketika kontak dengan pasien yang mempunyai penyakit infeksi,
41% responden dilaporkan menderita penyakit dermatitis yang diakibatkan oleh pekerjaan, 26%
responden menderita dermatitis akibat menggunakan sarung tangan, dan 2% responden
terdiagnosis alergi terhadap lateks 17
.
Berdasarkan Permenakertrans No.PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri
bahwa pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja di tempat kerja. Pekerja dan orang lain
yang memasuki tempat berisiko, wajib memakai atau menggunakan APD sesuai dengan potensi
bahaya dan risiko. Ketersediaan APD di tempat kerja harus menjadi perhatian managemen
perusahaan dan pekerja untuk mendorong terjadinya perubahan sikap pekerja. Semua fasilitas alat
pelindung diri yang diwajibkan terhadap tenaga perawat dan bidan. Alat pelindung diri harus
tersedia sesuai dengan faktor risiko bahaya yang ada di tempat kerja 18
. Dari hasil penelitian ini
terlihat bahwa ketersediaan APD di ruang bersalin tidak 100% tersedia lengkap. Hal ini sesuai
dengan penelitian Yuliana (2016) dan Nurhayati SA (2016) bahwa responden yang ketersediaan
APD lengkap cenderung cenderung menggunakan APD. Faktor ketersediaan merupakan faktor
yang memfasilitasi bidan untuk selalu menggunakan APD secara lengkap dan kondisi baik pada
saat proses persalinan normal. Hal ini dikarenakan dengan ketersediaan APD secara lengkap, bidan
dapat menggunakan APD secara lengkap saat menolong persalinan normal 11, 19
.
Dari hasil penelitian mengenai kepatuhan perawat dan bidan terhadap kewaspadaan standar
di Nigeria, diperoleh hasil bahwa faktor personal (53,7%) dan faktor institusi (81,6%) ditemukan
mempengaruhi praktik tindakan kewaspadaan standar. Selain itu diperoleh hubungan signifikan
antara tindakan kewaspadaan standar dengan ketersediaan APD. SOP dan kebijakan yang dibuat
harus menjawab kebutuhan tenaga kesehatan untuk mematuhi tindakan kewaspadaan standar,
terlepas dari pengetahuan mereka tentang bahaya infeksi, sehingga baik manajemen ataupun
institusi terkait harus melakukan setidaknya monitoring terhadap ketersediaan APD 20
.
Dari hasil kualitatif, belum ada pengawasan atau monitoring oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota di PMB mengenai PPI yang termasuk di dalamnya adalah APD sebagai komponen
utama kewaspadaan standar. Kunjungan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota hanya dilakukan untuk
penerbitan Surat Ijin Praktek Bidan. Dari hasil penelitian Supiana (2015) diketahui bahwa
monitoring mempengaruhi kebijakan penggunaan APD oleh dokter dan bidan di ruang bersalin dan
nifas. Demikian juga dengan evaluasi penggunaan APD memiliki hubungan yang signifikan
dengan pelaksanaan kebijakan penggunaan APD, terlihat bahwa kurangnya umpan balik supervisi
secara langsung, dalam arti sebagian tidak menerima umpan balik yang menjadi dasar untuk
koreksi kesalahan mereka 10
. Dari hasil penelitian Catu (2019) menyatakan bahwa ada hubungan
yang signifikan antara peraturan dengan penggunaan APD dimana responden yang mengatakan
adanya peraturan memiliki peluang 0,250 kali lebih tinggi untuk patuh menggunakan APD
dibanding dengan responden yang mengatakan tidak ada peraturan 21
. World Health Organization
(WHO) 2008 menyatakan bahwa peningkatan penerapan kewaspadaan standar akan menurunkan
risiko transmisi dengan meningkatkan lingkungan kerja yang aman dan sesuai dengan langkah
yang dianjurkan. Dibutuhkan kebijakan dukungan pimpinan untuk pengadaan sarana, pelatihan
untuk petugas kesehatan, dan penyuluhan untuk pasien serta pengunjung 22
.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 162
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil kuantitatif, APD yang paling sering digunakan oleh bidan dalam
menolong persalinan adalah apron, sarung tangan dan masker, serta sebagian besar bidan tidak
menggunakan APD secara lengkap. Sedangkan dari hasil kualitatif didapatkan bahwa alasan tidak
menggunakan APD, sebagian besar bidan menyatakan bahwa penggunaan kacamata pelindung
mengganggu penglihatan dan penggunaan sepatu boots cukup berat dan licin.
Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah bahwa diperlukan upaya
monitoring dan evaluasi secara rutin oleh pemerintah daerah, maupun organisasi profesi (Ikatan
Bidan Indonesia) untuk meningkatkan pengawasan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
(PPI) di Praktik Mandiri Bidan. Dan diperlukan adanya inovasi dalam model APD yang nyaman
dan aman digunakan bidan dalam menolong persalinan.
KETERBATASAN PENELITIAN
Hasil penelitian ini tidak menggambarkan wilayah karena jumlah sampel dalam penelitian
ini sangat terbatas.
DAFTAR PUSTAKA
1. Kementrian Kesehatan RI. Kepmenkes No.HK.01.07/MENKES/320/2020 Tentang Standar
Profesi Bidan. Kementerian Kesehatan RI 2020 hal. 55.
2. Spiritia. Infeksi Nosokomial dan Kewaspadaan Universal. 2006.
3. Yayasan Spiritia. Profilaksis Pasca Pajanan. Yayasan Spiritia. 2014;
4. Kementerian Kesehatan RI. Permenkes Nomo 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan
dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Nomor 27 Tahun 2017 2017.
5. Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.28 Tahun 2017, Tentang Izin
dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Kementerian Kesehatan RI 2017 hal. 9–15.
6. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Permenakertrans
No.PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri. PER.08/MEN/VII/2010 2010.
7. WHO. Health Care Worker Safety. 2003.
8. Kusman I. Laporan Akhir Penelitian Peneliti Muda Universitas Padjajaran : Hubungan
Pengetahuan, Sikap Dan Pelaksanaan Prosedur Kewaspadaan Universal Perawat Dalam
Pencegahan Penularan HIV-AIDS Di Puskesmas Tasikmalaya. Bandung; 2008.
9. Djauhari B. Faktor Yang Berhubungan Dengan Luka Tusuk Jarum Suntik Pada Bidan Desa Di
Kabupaten Mojokerto Tahun 2015. Universitas Airlangga; 2015.
10. Supiana N, Supriyatiningsih, Rosa EM. Pelaksanaan Kebijakan dan Penilaian Penggunaan
APD (Alat pelindung Diri) Oleh Dokter dan Bidan di Ruang Bersalin dan Nifas RSU PKU
Muhammadiyah Yogyakarta Unit I tahun 2014/2015. J UMY. 2015;4(1).
11. Yuliana SV, Hartanti RI, Prasetyowati I. Faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan Alat
Pelindung Diri secara Lengkap pada Bidan ( Studi di Wilayah Kerja Kabupaten Bondowoso ) (
Determinant of Complete Personal Protective Equipment Using for Midwives ( study in Work
Region of Bondowoso District. e-Jurnal Pustaka Kesehat. 2016;4(2):337–44.
12. Kementerian Kesehatan RI. Riskesdas 2013 Dalam Angka. Jakarta: Badan Litbang Kesehatan;
2013.
13. Musthafa WU, Darmawati. Pemakaian APD Pada Proses Pertolongan Persalinan Di Ruang
Bersalin Rumah Sakit Kota Banda Aceh. J Ilm Mhs Fak Keperawatan. 2016;1(1):1–6.
14. Departemen Kesehatan RI. Pedoman Pelaksanaan Kewaspadaan Universal di Pelayanan
Kesehatan. Jakarta: Departemen Kesehatan RI; 2010.
15. Noviana N. Universal Precaution: Pemahaman Tenaga Kesehatan Terhadap Pencegahan
HIV/AIDS. J Kesehat Reproduksi. 2017;8(2):143–51.
16. Istiqamah, Dwi Rahmawati. Pencegahan Infeksi Pada Pertolongan Persalinan Di Praktik
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 163
Mandiri Bidan Kota Banjarmasin. Proceeding Sari Mulia Univ Midwifery Natl Semin
[Internet]. 2019;135–47. Tersedia pada:
https://ocs.unism.ac.id/index.php/PROBID/article/view/35/45
17. Sasaki M, Kanda K. Glove Selection as Personal Protective Equipment and Occupational
Dermatitis among Japanese Midwives. J Occup Health. 2006;48:35–43.
18. Zubaidah T, Arifin, Jaya YA. Pemakaian Alat Pelindung Diri Pada Tenaga Perawat dan Bidan
Di Rumah Sakit Pelita Insani. J Kesehat Lingkung. 2015;12(2):291–8.
19. Nurhayati SA, Setyaningrum R, Fadillah NA. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan
Penggunaan Alat Pelindung Diri Pada Bidan Saat Melakukan Pertolongan Persalinan Normal. J
Publ Kesehat Masy Indones [Internet]. 2016;3(1):13–9. Tersedia pada:
https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/JPKMI/article/viewFile/2731/2380
20. Foluso O, Makuochi IS. Nurses and Midwives Compliance with Standard Precautions in
Olabisi Onabanjo University Teaching Hospital , Sagamu Ogun State. Iternational J Prev Med
Res. 2015;1(4):193–200.
21. Nurdiani CU, Krianto T. Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (apd) di laboratorium pada
mahasiswa prodi diploma analis kesehatan universitas mh thamrin. J Ilm Kesehat [Internet].
2019;11(September):88–93. Tersedia pada:
http://journal.thamrin.ac.id/index.php/jikmht/article/view/72/71
22. WHO. Penerapan Kewaspadaan Standar di fasilitas pelayanan kesehatan. 2008.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 164
KONTRIBUSI KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PERILAKU MASYARAKAT
TERHADAP MASALAH PENYAKIT INFEKSI PERNAPASAN
Ika Dharmayanti*,
Dwi Hapsari Tjandrarini,Olwin Nainggolan, Zahra
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
Jl. Percetakan Negara No.29 Jakarta Pusat
Corresponding email: [email protected]
THE CONTRIBUTION OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND COMMUNITY
BEHAVIOR TO RESPIRATORY DISEASES
ABSTRACT
Respiratory disease can infect people of all ages. These diseases are spread through saliva or secretion
droplets released by the patient when sneezing or coughing and through contaminated objects or surfaces.
Pneumonia is a lower respiratory tract infection, while COVID-19 can infect both the upper and lower
respiratory tracts. This study aims to determine the risk factors for the progression of pneumonia and
COVID-19, so it can calculate the fluctuation of diseases. The analysis used data from the Ministry of
Health, the COVID-19 Taskforce, the Central Bureau of Statistics, and the Ministry of Environment and
Forestry. The statistical test used was linear regression to determine the effect of behavioral and
environmental factors on pneumonia and COVID-19. The results show that livable houses, not doing
handwashing properly, and a combination of risky behavior, which is cigarette and alcohol consumption,
contributed 60% of the incidence of pneumonia. In COVID-19, 62% of the contributing factors are ex-
smokers who suffer from non-communicable diseases and the air quality index. This research shows that
healthy living behavior and environmental health are significant to reduce respiratory infections. Therefore
it is recommended to prioritizing behavior change and maintaining environmental health. Behavioral
changes that can be done are to have a healthy lifestyle such as frequent hand washing, not smoking, and
consuming alcohol, the importance of wearing masks when outside the home to minimize the exposure of
toxic substances in the air. The availability of livable houses is also necessary for the prevention of
respiratory diseases.
Keywords: Pneumonia, COVID-19, behavior, environmental health
ABSTRAK
Penyakit infeksi saluran pernapasan sering dialami oleh semua kelompok usia. Penyakit ini dapat menular
melalui percikan air liur atau droplet yang dikeluarkan penderita saat bersin atau batuk dan dari benda atau
permukaan yang sudah terkontaminasi. Penumonia merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan bawah,
sedangkan COVID-19 dapat menyerang saluran pernapasan atas dan bawah. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui faktor yang diprediksi berkontribusi terjadinya pneumonia dan COVID-19 sehingga dapat
menghitung naik turunnya jumlah kasus penyakit. Analisis menggunakan data hasil penelitian Kementerian
Kesehatan, Satuan Tugas COVID-19, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Uji statistik yang digunakan adalah regresi linear untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor
perilaku dan lingkungan terhadap penyakit pneumonia dan COVID-19. Hasil menunjukkan bahwa faktor
rumah layak huni, tidak mencuci tangan dengan benar, dan kombinasi perilaku berisiko yaitu merokok-
konsumsi alkohol berkontribusi sebesar 60% untuk kejadian penumonia. Pada penyakit COVID-19, sebesar
62% faktor yang penyebabnya adalah mantan perokok yang menderita penyakit tidak menular dan indeks
kualitas udara. Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku hidup sehat dan kesehatan lingkungan penting
untuk menurunkan penyakit infeksi saluran pernapasan. Oleh karena itu disarankan untuk mengutamakan
aspek perilaku dan kesehatan lingkungan. perunahan perilaku yang bisa dilakukan adalah berperilaku hidup
sehat seperti sering mencuci tangan, tidak merokok dan konsumsi alkohol, pentingnya menggunakan masker
saat berada di luar rumah untuk meminimalisir terpaparnya bahan beracun dalam udara ketersediaan rumah
layak huni juga diperlukan untuk pencegahan penyakit pernapasan..
Kata Kunci: Pneumonia, COVID-19, perilaku, kesehatan lingkungan
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 165
PENDAHULUAN
Infeksi saluran pernapasan adalah masuknya kuman atau mikroorganisme ke dalam tubuh
manusia dan berkembang biak menyerang di setiap bagian saluran pernapasan sehingga menimbulkan
gejala batuk, pilek yang disertai dengan demam. . Penyakit ini sangat mudah menular dan paling banyak
diderita oleh anak-anak dan orang-orang lanjut usia. Terdapat dua jenis infeksi saluran pernapasan,
yaitu infeksi saluran pernapasan atas (upper respiratory tract infections), seperti batuk pilek,
sinusitis, rhinitis, tonsillitis, radang tenggorokan, dan laringitis; infeksi saluran pernapasan bawah
(lower respiratory tract infections) seperti bronkitis, bronkiolitis, pneumonia,
dan tuberkulosis (TBC) (1).
Infeksi saluran pernapasan bisa terjadi secara tiba-tiba atau akut (ISPA) yang dapat terjadi di
saluran napas atas atau pun bawah, seperti flu, SARS, dan COVID-19 (2). Kelompok orang yang
rentan terhadap penyakit ISPA adalah anak-anak dan lansia, orang dewasa dengan sistem
kekebalan tubuh lemah, penderita ganguan jantung dan paru-paru, dan perokok aktif (3,4). Selain
itu, kurang menjaga kebersihan seperti tidak rutin mencuci tangan sebelum makan atau setelah
melakukan aktivitas di luar rumah, berada di tempat ramai (seperti di rumah sakit, sekolah atau
pusat perbelanjaan), atau sedang melakukan perjalanan ke daerah yang sedang banyak kasus
infeksi saluran pernapasan (3–5) dapat meningkatkan kemungkinan terpapar penyakit. Seperti
penyakit ISPA pada umumnya, penularan pneumonia dan COVID-19 dapat terjadi melalui kontak
dengan percikan air liur (droplet) penderita atau orang yang terinfeksi saat sedang berbicara, bersin
atau batuk. Selain melalui droplet, virus atau bakteri dapat menyebar melalui sentuhan dengan
benda yang terkontaminasi, atau berjabat tangan dengan penderita(6).
Penyakit menular yang dapat disebabkan oleh bakteri atau virus ini merupakan penyebab utama
kematian dan kesakitan di dunia. Jumlah kematian akibat infeksi saluran pernapasan akut (ISPA)
setiap tahun sekitar empat juta orang, yang mana 98% disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan
bawah (6). Penyakit pneumonia menyebabkan kematian 15% dari semua kematian anak dibawah
lima tahun (balita) dengan sebanyak 808.694 kematian pada tahun 2017 (3). Kasus pneumonia
(radang paru) di Indonesia berdasarkan laporan Riset Kesehatan Dasar 2018 dengan atau tanpa
foto dada (foto rontgen) oleh tenaga kesehatan dalam 1 tahun terakhir yang mengalami gejala
demam tinggi, batuk, kesulitan bernapas, sebesar 4%, dengan proporsi kasus pada balita sebanyak
4,8% (7). Menurut laporan Subdit ISPA Tahun 2017, kasus pneumonia per-1000 balita di Indonesia
sebesar 20,56%, sedangkan pada tahun 2018 jumlah kasus sebanyak 20,06%, dengan perkiraan
kasus pneumonia secara nasional sebesar 3,55% (8).
Penyakit COVID-19 mulai terdeteksi di Indonesia pada bulan Maret 2020. Hingga tanggal
27 September 2020, kasus yang terjadi sebanyak 275.213 kasus dengan jumlah kematian 10.386
orang atau sekitar 3,8% (9). Infeksi penyakit COVID-19 dapat menimbulkan beberapa gejala,
seperti gejala ringan, sedang, atau berat. Gejala utama yang muncul adalah demam, batuk, dan
kesulitan bernafas. Untuk gejala penyakit ringan bahkan tidak disertai demam dengan gejala
penyakit yang tidak spesifik. Penyakit ini bisa meningkat menjadi penumonia ringan, dan
pneumonia berat pada pasien dewasa (10).
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti ingin mengetahui faktor apa saja yang
berhubungan dengan kejadian penyakit pneumonia dan COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang diprediksi berkontribusi terjadinya pneumonia dan
COVID-19 sehingga dapat menghitung kenaikan maupun penurunan jumlah kasus penyakit.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 166
METODE
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data agregasi provinsi yang telah
dipublikasikan dalam laporan. Sumber data yang digunakan adalah (1) Publikasi Riset Kesehatan
Dasar 2018 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan; (2)
Publikasi Data kasus COVID-19 oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19; (3) Publikasi Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup 2017 oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan; dan (4)
Publikasi rumah layak huni oleh Badan Pusat Statistik
Dua variabel terikat yang dibahas dalam penelitian ini adalah prevalensi penumonia dan
persentase kasus COVID-19. Variabel bebas yang digunakan adalah:
1. Persentase perilaku mencuci tangan dengan benar. Kriteria benar yaitu mencuci tangan pakai
sabun dengan air mengalir sebelum menyiapkan makanan, setiap kali tangan kotor
(memegang uang, binatang dan berkebun), setelah buang air besar, setelah menceboki
bayi/anak, setelah menggunakan pestisida/insektisida, sebelum menyusui bayi, dan sebelum
makan (7)
2. Komposit persentase perilaku merokok dan persentase konsumsi minuman beralkohol.
Perilaku berisiko yaitu gabungan dari persentase kebiasaan merokok setiap hari dengan
persentase komsumsi minuman beralkohol selama 1 bulan terakhir
3. Komposit persentase Penyakit Tidak Menular (PTM) dan persentase perilaku merokok.
Kondisi berisiko adalah gabungan dari persentase mantan perokok dan persentase yang
menderita PTM (hipertensi, diabetes, jantung, dan stroke)
4. Persentase rumah layak huni. Penilaian rumah berdasarkan tujuh indicator komposit terkait
perumahan, yaitu: akses air layak, akses sanitasi layak, sufficient living area (luas lantai
perkapita > 7,2 m2), jenis lantai, jenis dinding, jenis atap, dan penerangan listrik (8).
5. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU). IKU merupakan hasil pengukuran dari dua parameter
pencemar utama udara yaitu sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen dioksida (NO2) (11).
Nilai yang digunakan dalam analisis adalah angka dalam persen dan skor untuk IKU. Nilai
tersebut adalah hasil analisis agregasi tingkat provinsi. Besaran hubungan dan arah hubungan
antara variabel bebas dan terikat dilihat menggunakan uji korelasi COVID-19. Dilanjutkan dengan
uji regresi linear untuk mengestimasi dan melihat hubungan semua variabel bebas secara bersama-
sama dengan variabel terikat melalui suatu persamaan yang dihasilkan dari analisis.
HASIL PENELITIAN
Tabel 1 memperlihatkan hasil desktiptif analisis data yang digunakan dalam penelitian.
Informasi meliputi nilai minimum dan maksimum, nilai rata-rata, standard deviasi, nilai skewness
dan kurtosis.
Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif Penelitian
Variable (N=34) Minimum Maksimum Rata-
rata
Std.
Deviasi Skewness Kurtosis
Pneumonia 2,60 7,00 4,24 1,14 0,92 0,30
COVID19 0,13 25,44 2,94 5,09 3,38 12,55
Tidak mencuci tangan
dengan benar 32,60 79,60 53,52 10,22 0,406 0,383
Komsumsi rokok dan alkohol 21,90 39,50 28,55 4,20 0,84 0,79
Mantan perokok dan PTM 30,52 66,96 49,44 8,84 0,23 -0,28
Indeks kualitas udara 53,50 96,00 88,71 7,78 -3,09 12,59
Rumah layak huni 58,23 99,46 93,90 7,92 -3,55 13,85
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 167
Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata prevalensi penyakit pneumonia 4,24. Nilai tersebut
lebih tinggi dibandingkan persentase penyakit COVID-19 dengan nilai rata-rata 2,94. Perbedaan
masalah antar provinsi terlihat sangat lebar pada persentase COVID. Nilai rata-rata indeks kualitas
udara adalah 88,71, hal ini menunjukkan kualitas udara di Indonesia pada umumnya sangat baik.
Demikian juga dengan rata-rata persentase rumah di Indonesia sudah layak huni (93,9).
Gambar 1
Proporsi Penyakit Pneumonia dan COVID-19 di Indonesia
Identifikasi kecenderungan tinggi rendahnya status penyakit pneumonia dan COVID-19
dengan menggunakan perhitungan nilai rata-rata persentase dan standar deviasi, maka
dikelompokkan dalam tiga kategori: yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Untuk pneumonia rentang
pengukuran dari tinggi ke rendah adalah ≥ 5,38 hingga < 3,09, sedangkan untuk COVID-19
rentang pengukuran dari tinggi ke rendah adalah ≥8,03 hingga < -2,14. Gambar 1 menunjukkan
penyakit pneumonia dan COVID-19 paling banyak berada pada kelompok sedang (76,5% dan
94,1%). Penyakit pneumonia lebih banyak ditemukan pada kelompok tinggi (14,7%) dibandingkan
COVID-19 (5,9%). Sedangkan penyakit COVID-19 tidak ditemukan pada kelompok rendah.
Tabel 2. Hasil Uji Korelasi Pneumonia dan COVID-19
Variable (N=34) Pneumonia P-value COVID19 P-value
Tidak mencuci tangan dengan benar 0,467 0,005* -0,276 0,115
Perilaku merokok dan mengonsumsi
alkohol 0,409 0,016* -0,223 0,204
Mantan perokok dan menderita
PTM -0,395 0,021* 0,416 0,014*
Rumah layak huni -0,684 0,000* 0,186 0,292
Indeks Kualitas Udara 0,097 0,584 -0,767 0,000*
Berdasarkan Tabel 2 faktor perilaku tidak mencuci tangan dengan benar serta perilaku
merokok dan mengonsumsi alkohol suatu wilayah berkorelasi positif dengan prevalensi penyakit
pneumonia suatu wilayah, artinya semakin banyak yang tidak mencuci tangan dengan benar dan
mengonsumi rokok-alkohol dapat meningkatkan prevalensi penyakit pneumonia. Sedangkan
jumlah rumah yang layak huni di suatu wilayah berkorelasi negatif dengan prevalensi pneumonia
suatu wilayah yang artinya semakin banyak rumah yang layak huni akan menurunkan
kemungkinan penyakit pneumonia.
Hal yang dapat menjadi perhatian pada penyakit COVID-19, jumlah mantan perokok dan
jumlah penderita PTM pada suatu wilayah berkorelasi positif dengan COVID-19, artinya
peningkatan mantan perokok yang mengidap PTM akan meningkatkan kemungkinan terpapar
Tinggi Sedang Rendah
14,7
76,5
8,8 5,9
94,1
Pneumonia Covid-19 (per-21092020)
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 168
COVID-19. Indeks kualitas udara berkorelasi negative dengan COVID-19, yang berarti semakin
baik kualitas udara akan menurunkan kemungkinan penyakit COVID-19.
Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Pneumonia dan COVID-19
Variabel Koefisien
Korelasi
Standar
Error R R Square F P-Value t VIF
Pneumonia 11,118 3,017 0,773 0,598 14,879 0,000 3,685
Tidak mencuci tangan dengan benar -0,006 0,018 0,741 -0,334 1,928
Komsumsi rokok dan alkohol 0,098 0,031 0,004 3,108 1,013
Rumah layak huni -0,100 0,023 0,000 -4,331 1,914
COVID-19 38,704 8,524 0,787 0,619 25,225 0,000 4,541
Mantan perokok dan PTM 0,106 0,068 0,126 1,574 1,120
Indeks Kualitas Udara -0,462 0,077 0,000 -6,028 1,120
Hasil Tabel 3, menghasilkan persamaan yang diperoleh untuk prediksi penyakit pneumoni
adalah:
Y = 11,118 – 0,006 tidak mencuci tangan dengan benar + 0,098 konsumsi rokok dan alcohol
– 0,1
rumah layak huni.
Terdapat hubungan yang kuat antara antara pneumonia dengan perilaku tidak mencuci tangan
dengan benar, konsumsi rokok dan alcohol serta rumah layak huni (R= 0,77), dengan pengaruh
variable-variabel tersebut terhadap penyakit penumonia sebesar 60%.
Persamaan yang diperoleh untuk prediksi penyakit COVID-19 adalah:
Y = 38,704 + 0,106 mantan perokok PTM – 0,462 indeks kualitas udara.
Hubungan yang kuat juga terjadi antara mantan perokok yang menderita PTM dan indeks kualitas
udara (R=0,79), dengan pengaruh variable terhadap penyakit COVID-19 sebesar 62%.
Walaupun persentase tidak mencuci tangan dengan benar serta persentase mantan perokok
dan PTM tidak mempunyai hubungan yang bermakna dengan kejadian penyakit, akan tetapi faktor
tersebut dianggap penting dalam penyebaran penyakit, maka kedua variable tersebut tetap
dimasukkan dalam model.
PEMBAHASAN
Hubungan Status Kesehatan Wilayah dengan Status Pneumonia
Secara umum, kasus pneumonia di Indonesia masih masih cukup tinggi. Perilaku cuci tangan
dengan benar menggunakan sabun dan air mengalir (CTPS) merupakan salah satu dari lima
program pemerintah tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). STBM adalah suatu
upaya untuk mengubah perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat (12). Cuci
tangan menggunakan sabun dan air mengalir terbukti efektif dalam pencegahan penyakit diare,
ispa, pneumonia dan infeksi cacing (13). Dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
akan memutus mata rantai penyebaran penyakit karena tangan seringkali menjadi agen pembawa
kuman penyakit baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung (menggunakan
permukaan benda yang sudah terpapar kuman penyakit) (14–16).
Perilaku merokok setiap hari dan konsumsi alkohol dapat secara rutin dapat meningkatkan
risiko penyakit pneumonia. Hal ini terjadi karena merokok dan mengonsumsi alkohol dapat
merusak sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh menjadi lebih rentan terkena infeksi (17,18).
Rokok dan alkohol dapat merusak paru-paru sehingga memicu berbagai macam penyakit paru-paru
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 169
diantaranya pneumonia (19,20). Bahkan, penyakit pneumonia akan lebih serius pada pengguna
alkohol. Dengan berhenti merokok dan mengonsumsi alkohol dapat mencegah kerusakan paru
lebih lanjut.
Kesehatan lingkungan pemukiman dan perumahan juga dapat menurunkan risiko penyakit
pneumonia. Penilaian rumah layak huni yang dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang No.1
Tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman, diharapkan dapat melindungi penghuninya dari
penularan penyakit serta kecelakaan (8). Prasarana dan sarana yang tersedia dalam rumah layak
huni harus memenuhi standard untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, aman dan
nyaman. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kondisi rumah berhubungan dengan kejadian
pneumonia. Asap dan debu akibat penggunaan bahan bakar untuk memasak, asap rokok maupun
penggunaan obat anti nyamuk akan memicu penyakit pneumonia terutama pada balita (21,22).
Hubungan Status Kesehatan Wilayah dengan penyakit COVID-19
Walaupun penyakit COVID-19 baru mewabah pada akhir 2019, akan tetapi jumlah
penderitanya sudah mencapai jutaan orang di dunia. Secara umum, kasus COVID-19 di Indonesia
cukup tinggi dengan proporsi 94,1% berada pada level sedang. Faktor yang mempengaruhi
penyakit COVID-19 dalam penelitian ini adalah mantan perokok yang menderita PTM dan indeks
kesehatan udara yang berkontribusi pada 62% kejadian penyakit dan sisanya berasal dari faktor
lainnya.
Sama halnya dengan perokok aktif, mantan perokok juga berisiko menderita penyakit,
salah satunya COVID-19. Dengan demikian, mantan perokok yang menderita PTM sangat berisiko
tinggi terpapar COVID-19, karena penderita PTM sangat rentan terkena infeksi yang disebabkan
menurunnya imunitas tubuh. Hasil review yang dilakukan oleh WHO menyebutkan bahwa dengan
adanya penyakit penyerta atau komorbid PTM menyebabkan seseorang menjadi berisiko tinggi
terkena penyakit yang lebih parah terkait COVID-19 bahkan hingga kematian (18,23). Dengan
demikian, sangat dianjurkan untuk hidup lebih sehat dengan menghentikan kebiasan merokok,
sebelum rokok memberikan efek buruk pada organ dalam tubuh.
Pengaruh lingkungan yang dianalisis pada penelitian ini yang memiliki hubungan dengan
penyakit COVID-19 adalah indeks kualitas udara. Penilaian IKU menggunakan parameter SO2
yang merupakan emisi dari industri dan kendaraan diesel, bahan bakar solar serta bahan bakar yang
menggunakan sulphur; dan parameter NO2 merupakan hasil emisi dari kendaraan bermotor yang
menggunakan bensin (11). Beberapa kajian menyebutkan bahwa tingkat polusi udara yang tinggi
dapat menjadi salah satu risiko dalam kasus COVID-19 yang fatal (24–26). Penurunan kualitas
udara akan berdampak pada kesehatan manusia yaitu menurunkan imunitas tubuh, sedangkan
paparan jangka panjang dapat merusak paru-paru dan jantung (18). Dengan adanya penyakit
penyerta inilah seseorang lebih rentan terpapar COVID-19, menderita penyakit COVID-19 yang
lebih parah, hingga meningkatkan risiko kematian.
Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya tersedia data agregasi provinsi sehingga
tidak dapat memberi gambaran lebih detil misalnya Kabupaten/Kota. Dengan demikian tidak dapat
melihat hubungan antar variable secara individu yang seharusnya dapat memberi gambaran
hubungan yang lebih riil.
KESIMPULAN DAN SARAN
Pentingnya menanamkan perilaku sehat sejak dini yaitu: perilaku cuci tangan dengan benar,
tidak membiasakan mengonsumsi rokok dan alkohol karena dapat merusak sistem kekebalan tubuh
sehingga tubuh menjadi lebih rentan terkena infeksi. Selain itu perlu mengondisikan rumah layak
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 170
huni. Rumah layak huni tidak berarti mahal. Kondisi itu semua dapat menurunkan kejadian
penyakit pneumonia di Indonesia
Kejadian COVID-19 di Indonesia menunjukkan adanya hubungan penyakit tidak menular
dengan penyakit menular. Status mantan perokok karena menderita PTM, kondisi yang sudah
terlambat. Didukung pula dengan indeks kualitas udara yang rendah. Kedua hal tersebut
meningkatkan kejadi COVID-19. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor perilaku dan kualitas
lingkungan sangat berpengaruh dalam peningkatan kasus penyakit infeksi pernapasan di
masyarakat.
Dengan demikian, penelitian ini menyarankan untuk mengutamakan perilaku hidup bersih
dan sehat yaitu sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tidak merokok dan tidak
mengonsumsi alkohol agar terhindar dari penyakit PTM. Berhentilah merokok sesegera mungkin,
jangan menunggu setelah menderita PTM. Sangat disarankan menggunakan masker saat di luar
rumah agar tehindar dari paparan bahan beracun dalam udara. Fasilitas rumah layak huni juga
diperlukan untuk mengendalikan penyakit saluran pernapasan, yaitu kecukupan ventilasi dan selalu
membuka jendela kamar tidur.
DAFTAR PUSTAKA
1. Healthline Editorial Team. Acute Respiratory Infection [Internet]. Healthline Media. 2019
[cited 2020 Sep 30]. Available from: https://www.healthline.com/health/acute-respiratory-
disease
2. Alodokter Editorial Tim. Infeksi Saluran Pernapasan [Internet]. Alodokter.com. 2020 [cited
2020 Sep 29]. Available from: https://www.alodokter.com/infeksi-saluran-pernapasan
3. World Health Organization. Pneumonia [Internet]. WHO Fact sheet. 2019 [cited 2020 Sep
30]. p. 2–5. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia
4. World Health Organization. Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus [Internet]. World
Health Organization. 2020. Available from: https://www.who.int/indonesia/news/novel-
coronavirus/qa-for-public
5. Burhan E, Isbaniah F, Susanto AD, Aditama TY, Sartono TR, Sugiri YJ, et al. Pneumonia
Covid-19: Diagnosis dan Penatalaksanaan di Indonesia. Jakarta: Perhimpunan Dokter Paru
Indonesia; 2020. 58 p.
6. WHO. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Saluran Pernapasan Akut ( ISPA ) yang
Cenderung Menjadi Epidemi dan Pandemi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pedoman
Interim WHO [Internet]. 2007;12. Available from:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69707/14/WHO_CDS_EPR_2007.6_ind.pdf
7. Kementerian Kesehatan. Laporan Nasional Riskesdas 2018. Vol. 3, Lembaga Penerbit
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB). 2019. 572 p.
8. Kemenkes RI. Profil Kesehatan Indonesia 2018 [Indonesia Health Profile 2018]. Jakarta:
Kementerian Kesehatan; 2019. 207 p.
9. Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Analisis Data Covid-19 Indonesia. Jakarta; 2020.
10. Yuliana. Corona virus disease (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur. Wellness adn Heal
Mag. 2020;2(February):187–92.
11. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Indonesia 2017. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia. Jakarta; 2018.
12. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Pelaksanaan Teknis STBM Tahun
2012 [Internet]. Kesehatan. 2012. 1–72 p. Available from:
http://stbm.kemkes.go.id/public/docs/reference/5b99c4c2576e12f4c9a2019139312658b2f37
04c9abc5.pdf
13. The Global Handwashing Partnership. Why Handwashing [Internet]. 2020 [cited 2020 Oct
8]. p. 1–8. Available from: https://globalhandwashing.org/about-handwashing/why-
handwashing/health/
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 171
14. Chiu NC, Chi H, Tai YL, Peng CC, Tseng CY, Chen CC, et al. Impact of wearing masks,
hand hygiene, and social distancing on influenza, enterovirus, and all-cause pneumonia
during the coronavirus pandemic: Retrospective national epidemiological surveillance
study. J Med Internet Res. 2020;22(8).
15. Rani SVM, Garina LA, Ekowati R. Hubungan Antara Status Imunisasi , Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat Melalui Cara Mencuci Tangan dengan Kejadian Pneumonia pada Balita (
Suatu Kajian Kasus di RSUD Al-Ihsan Kabupaten Bandung Tahun 2016). 2016;2(2):594–
601.
16. Aiello AE, Coulborn RM, Perez V, Larson EL. Effect of Hand Hygiene on Infectious
Disease Risk in the Community Setting : A Meta-Analysis. 2008;98(8):1372–82. Available
from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334143/WHO-2019-nCoV-Non-
communicable_diseases-Evidence-2020.1-eng.pdf
17. Vertava Health Editorial Team. Effects Of Alcohol On The Lungs [Internet]. 2020 [cited
2020 Oct 8]. Available from: https://vertavahealth.com/alcohol/effects-on-lungs/
18. World Health Organization. Responding to non-communicable diseases during and beyond
the COVID-19 pandemic. 2020.
19. Simou E, Britton J, Leonardi-Bee J. Alcohol and the risk of pneumonia: A systematic
review and meta-analysis. BMJ Open. 2018;8(8):1–10.
20. Baskaran V, Murray RL, Hunter A, Lim WS, McKeever TM. Effect of tobacco smoking on
the risk of developing community acquired pneumonia: A systematic review and meta-
analysis. PLoS One. 2019;14(7):1–18.
21. Anwar A, Dharmayanti I, Teknologi P, Kesehatan I, Badan M, Kesehatan P. Pneumonia
pada Anak Balita di Indonesia Pneumonia among Children Under Five Years of Age in
Indonesia. 2013;(29):359–65.
22. Budiati E. Kondisi rumah dan pencemaran udara dalam rumah sebagai faktor risiko
kejadian pneumonia balita. Yars Med J [Internet]. 2016;20(2):87–101. Available from:
http://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/jurnal-fk-yarsi/article/view/163/99
23. Hernández-Galdamez DR, González-Block MÁ, Romo-Dueñas DK, Lima-Morales R,
Hernández-Vicente IA, Lumbreras-Guzmán M, et al. Increased Risk of Hospitalization and
Death in Patients with COVID-19 and Pre-existing Noncommunicable Diseases and
Modifiable Risk Factors in Mexico. Arch Med Res. 2020;(December 2019).
24. Farhan Bashir M, Jiang MA B, Bilal, Komal B, Adnan Bashir M, Hassan Farooq T, et al.
Correlation between environmental pollution indicators and Covid-19 pandemic: A brief
study in California context. Environ Res. 2020;187.
25. Frontera A, Cianfanelli L, Vlachos K, Landoni G, Cremona G. Severe air pollution links to
higher mortality in COVID-19 patients: The ―double-hit‖ hypothesis. J Infect [Internet].
2020;81(2):255–9. Available from: https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.05.031
26. Zhu Y, Xie J, Huang F, Cao L. Association between short-term exposure to air pollution
and COVID-19 infection: Evidence from China. Sci Total Environ [Internet].
2020;727(December 2019):138704. Available from:
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138704
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 172
PREVALENSI PENYAKIT JANTUNG PADA USIA PRODUKTIF MENJADI
ANCAMAN TERHADAP KUALITAS BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA:
TINJAUAN LITERATUR
Basuki Rachmat
*, Khadijah Azhar
National Institute of Research and Development, Ministry of Health of Republic of Indonesia
Jl. Percetakan Negara No.29A, Jakarta Pusat
Corresponding email: [email protected]
PREVALENCE OF HEART DISEASE IN PRODUCTIVE AGE: THREATS TO THE
QUALITY OF DEMOGRAPHIC BONUSES IN INDONESIA
ABSTRACT
A country is said to experience a demographic bonus if two people of productive age (15-64) bear one
unproductive person (less than 15 years and 65 years or more). Indonesia has a potential demographic
bonus if most of the productive age suffer from heart disease, then the benefits of the demographic dividend
in Indonesia cannot run optimally. This literature review aims to discuss the risk factors associated with the
incidence of heart disease in productive age in Indonesia. The data sources are secondary data from reports
on the results of Basic Health Research since 2007, 2013 and 2018 and the BPS Report on the projected
demographic bonus. The data were analyzed by translating in tabular and graphic form. Scientific databases
such as Google Scholar were chosen as databases for accessing various articles in open journals. They are
using a qualitative approach and descriptive data analysis from a database in the form of articles published
in the last 15 years (2005-2019) on Google Scholar. Based on the study of the Basic Health Research reports
in 2007, 2013, and 2018. It was found that the prevalence of heart disease in Indonesia has tended to
increase at a productive age in the last ten years. Physical and eating patterns that are not as recommended.
The increasing prevalence of heart disease in productive age has the potential to reduce the quality of the
demographic bonus in Indonesia. From the literature analysis, it was found that the increasing prevalence of
heart disease would increase the number of people with heart disease, as evidenced by the increase in the
cost of financing for the treatment of heart disease in the last ten years.So that it requires optimal
promotional and preventive efforts to reduce the risk of heart disease at a a productive age, namely at the
age of 15 - 64 years.
Keywords: Productive age, heart disease, smoking behavior, Demographic Bonus, Indonesia
ABSTRAK
Sebuah negara dikatakan mengalami bonus demografi jika dua orang penduduk usia produktif (15-64)
menanggung satu orang tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun atau lebih). Indonesia memiliki
bonus demografi yang potensial, apabila sebagian besar usia produktif menderita penyakit jantung, maka
maanfaat bonus demografi di Indonesia tidak dapat berjalan secara optimal. Tinjauan literatur ini bertujuan
untuk membahas tentang faktor-faktor berisiko yang berhubungan dengan kejadian Penyakit Jantung pada
usia produktif di Indonesia. Sumber data adalah data sekunder laporan hasil Riset Kesehatan Dasar sejak
tahun 2007, 2013, dan 2018 dan Laporan BPS tentang proyeksi bonus demografi. Data tersebut dianalisis
dengan menterjemahkan dalam bentuk tabel dan gerafik. Databes ilmiah seperti Google Cendekia dipilih
sebagai basis data untuk mengakses berbagai artikel pada jurnal terbuka. Mengunakan pendekatan kualitatif
dan analisis data secara deskriptif dari database berupa artikel yang diterbitkan dalam kurun waktu 15 tahun
terakhir (2005-2019) di Google Cendekia.Berdasarkan analisis dari Laporan hasil Riset Kesehatan Dasar
tahun 2007, 2013, dan 2018 di dapatkan prevalensi penyakit jantung di Indonesia cenderung meningkat pada
usia produktif dalam sepuluh tahun terakhir, prevalensi ini salah satunya di sebabkan karena meningkatnya
perilaku merokok pada usia produktif, kurangnya aktifitas fisik dan pola makan yang tidak sesuai anjuran.
Meningkatnya prevalensi penyakit jantung pada usia produktif, maka berpotensi terhadap penurunan kualitas
bonus demografi di Indonesia. Dari analisis literatur diperoleh dengan meningkatnya prevalensi penyakit
jantung maka jumlah penderita penyakit jantung akan bertambah, terbukti dengan bertambahnya bebab
pembiayaan untuk penanganan penyakin jantung dalam sepuluh tahun terakhir. Sehingga di perlukan upaya-
upaya promotif dan preventif yang optimal untuk menekan resiko terkena penyakit jantung pada usia
produktif, yaitu di usia 15 – 64 tahun.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 173
Kata Kunci: Usia produktif, penyakit jantung, perilaku merokok, Bonus Demografi, Indonesia
PENDAHULUAN
Bonus demografi (demographic dividend) adalah keuntungan ekonomis yang disebabkan
oleh menurunnya angka ketergantungan sebagai hasil proses penurunan fertilitas jangka panjang.1
Transisi demografi menurunkan proporsi umur penduduk muda dan meningkatkan proporsi
penduduk usia kerja, dan ini menjelaskan hubungan pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan
ekonomi. Penurunan proporsi penduduk muda mengurangi besarnya investasi untuk pemenuhan
kebutuhannya, sehingga sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga.2
Bonus demografi sering dikaitkan dengan suatu kesempatan yang hanya akan terjadi satu
kali saja bagi semua penduduk negara yakni the window of opportunity.3 Kesempatan yang
diberikan oleh bonus demografi ini berupa tersedianya kondisi atau ukuran yang sangat ideal pada
perbandingan antara jumlah penduduk yang produktif dengan yang non-produktif.4 Pada saat itu
angka ketergantungan adalah yang terendah, selama usia penduduk tersebut, yang biasanya terletak
dibawah 50 persen. The window of opportunity ini hanya terbuka satu kali saja dalam sejarah suatu
bangsa, dan terbuka dalam waktu yang sangat singkat, yakni satu atau dua dekade saja sampai
jumlah orang tua meningkatkan angka ketergantungan. Jadi terbukanya the window of opportunity
yang menyediakan kondisi ideal untuk meningkatkan produktivitas ini harus dimanfaatkan sebaik-
baiknya bagi pemerintah suatu negara apabila ingin meningkatkan kesejahteraan penduduknya.5
Menurut Ahli Demografi, Sri Hartati Hambali (2009), ―bonus demografi hanya akan terjadi kalau
ada upaya rekayasa demografi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM (human capital
deepening). Kualitas ini bukan hanya menyangkut pendidikan, tetapi juga aspek gizi, kesehatan,
dan soft skill sehingga pendekatan kebijakannya juga harus life cycle approach dan lintas sektor
karena investasi modal manusia ini sifatnya investasi sosial jangka panjang yang hasilnya (return
on investment) baru akan bisa dinikmati dalam 30 tahun‖.6
Penyakit jantung merupakan salah satu penyakit yang sering terjadi di Indonesia, dua
diantaranya adalah penyakit jantung koroner (PJK) dan gagal jantung. Penyakit jantung koroner
adalah salah satu jenis penyakit yang disebabkan oleh ketidakmampuan arteri baik akut maupun
kronis untuk mengalirkan darah ke miokardium yang disebabkan oleh gangguan patologis pada
sistem arteri koroner.6,7
Ada beberapa faktor risiko Penyakit jantung Koroner, secara umum dibagi
menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah faktor risiko perilaku seperti kebiasaan
merokok, aktivitas fisik, pola makan yang tidak sehat dan konsumsi minuman beralkohol.
Kelompok kedua adalah faktor risiko metabolik seperti peningkatan tekanan darah, peningkatan
kandungan gula darah, peningkatan kandungan lemak dalam darah, kelebihan berat badan (over
weight) dan Kegemukan (obesity). Kelompok ke tiga adalah faktor risiko lainnya seperti
kemiskinan dan pendidikan yang rendah, usia lanjut, jenis kelamin, keturunan, faktor pisikologi
(seperti stress, depresi) dan faktor lain (seperti kelebihan homosistein).8–10
Gagal jantung didefinisikan sebagai kondisi dimana jantung tidak lagi dapat memompakan
cukup darah ke jaringan tubuh.11
Keadaan ini dapat timbul dengan atau tanpa penyakit jantung.
Gangguan fungsi jantung dapat berupa gangguan fungsi diastolik atau sistolik, gangguan irama
jantung, atau ketidaksesuaian preload dan afterload. Keadaan ini dapat menyebabkan kematian
pada pasien.12
Gagal jantung dapat dibagi menjadi gagal jantung kiri dan gagal jantung kanan.
Gagal jantung juga dapat dibagi menjadi gagal jantung akut, gagal jantung kronis dekompensasi,
serta gagal jantung kronis. Gagal jantung merupakan tahap akhir dari seluruh penyakit jantung dan
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 174
merupakan penyebab peningkatan morbiditas dan mortalitas pasien jantung.13,14
Gagal jantung
merupakan penyebab kematian yang cukup besar. Data-data di Pusat Jantung Nasional Harapan
Kita (PJNHK) sejak tahun 2003 menunjukan angka hospitalisasi pasien dengan diagnosa gagal
jantung yang semakin meningkat berkisar antara 1200-1300 pasien per tahun dengan angka
mortalitas yang juga terus meningkat dan mencapai 7.5 % pada tahun 2007.15
Pada tahun 2008 penyakit tidak menular merupakan penyebab kematian terbesar di dunia
yaitu sebesar 63% dari 57 juta kematian, dimana penyakit kardiovaskular, diabetes, kanker, dan
penyakit pernapasan kronis menjadi penyebab dari 36 juta kematian.16
Angka kematian ini
mengalami peningkatan di tahun 2016, kematian terbesar akibat penyakit tidak menular menjadi
sebesar 71% dari 57 juta kematian. Dimana penyakit utama yang bertanggung jawab kejadian ini
adalah penyakit kardiovaskular sebesar 17,9 juta kematian (44%).17
Penyakit kardiovaskuler juga
diestimasikan menjadi penyebab terbesar (35%) dari kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak
menular di Indonesia.17
Menurut data Global Burden Diseases tahun 2010 penyakit jantung
merupakan penyebab kematian kedua terbesar (8,11%) setelah stroke di Indonesai.18
Faktor risiko
merokok berkontribusi terhadap 6,92% dari kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung.
Angka kematian yang disebabkan kedua penyakit tersebut adalah 45,24 orang per-100.000
penduduk.19
Kesehatan merupakan salah satu sektor yang mendukung agar bonus demografi terlaksana
dengan maksimal, salah satunya adalah dengan upaya pencegahan terjadinya penyakit jantung di
Indonesia. Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2007, 2013 dan 2018, dapat digunakan untuk
menggambarkan pevalensi penyakit jantung pada usia produktif (15-64 tahun) dan faktor-faktor
penyebabnya sebagai upaya pencegahan. Oleh karena itu, tulisan ini di buat utuk mendeskripsikan
lebih lanjut tentang peningkatan prevalensi penyakit jantung, tren faktor risiko penyebabnya, beban
pembiayaan, serta upaya promotif dan preventif yang telah dilakukan untuk pengendalian kejadian
penyakit jantung guna memasuki periode bonus demografi (tahun 2020).
METODE
Penelitian ini adalah tinjauan literatur yang membahas tentang prevalensi, faktor-faktor dan
dampak terkait penyakit jantung. Faktor perilaku seperti kebiasaan merokok, aktivitas fisik,
konsumsi makanan berisiko dan konsumsi minuman beralkohol. Faktor risiko metabolik yang di
bahas pada artikel ini adalah seperti peningkatan tekanan darah, peningkatan kandungan gula
darah, peningkatan kandungan lemak dalam darah, kelebihan berat badan (over weight) dan
Kegemukan (obesity). Kelompok ke tiga adalah faktor risiko lainnya seperti kemiskinan dan
pendidikan yang rendah, usia lanjut, jenis kelamin, keturunan, faktor pisikologi (seperti stress,
depresi) dan faktor lain (seperti kelebihan homosistein).
Sumber data adalah data sekunder laporan hasil Riset Kesehatan Dasar sejak tahun 2007,
2013, dan 2018. Definisi porasional untuk penyakit jantung pada laporan hasil Riset Kesehatan
Dasar sejak tahun 2007, Untuk kasus penyakit jantung, riwayat pernah mengalami gejala penyakit
jantung dinilai dari 5 pertanyaan dan disimpulkan menjadi 4 gejala yang mengarah ke penyakit
jantung, yaitu penyakit jantung kongenital, angina, aritmia, dan dekompensasi kordis. Responden
dikatakan memiliki gejala jantung jika pernah mengalami salah satu dari 4 gejala termaksud.
Definisi porasional untuk penyakit jantung pada laporan hasil Riset Kesehatan Dasar sejak tahun
2013, Penyakit jantung pada orang dewasa yang sering ditemui adalah penyakit jantung koroner
dan gagal jantung. Definisi porasional untuk penyakit jantung pada laporan hasil Riset Kesehatan
Dasar sejak tahun 2018, Penyakit jantung adalah semua jenis penyakit jantung termasuk kelainan
jantung bawaan yang didiagnosis oleh dokter.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 175
Data tersebut dianalisis menggunakan literature ilmiah. Google Cendekia dipilih sebagai
basis data untuk mengakses berbagai artikel pada jurnal terbuka. Penelitian ini menerapkan
pendekatan kualitatif dan analisis data secara deskriptif dari database berupa artikel yang
diterbitkan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir (2005-2019) di Google Cendekia. Tinjauan
literatur ini bertujuan untuk membahas tentang perilaku berisiko, faktor risiko metabolik dan faktor
risiko lainnya yang berhubungan dengan kejadian Penyakit Jantung 2007, 2013, dan 2018.
HASIL PENELITIAN
Hasil proyeksi penduduk Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
menunjukkan bahwa Indonesia akan mengalami Bonus Demografi pada tahun 2020-2030 20
. Hal
ini dapat dilihat dari gambar proyeksi piramida penduduk Indonesia sejak tahun 2010 hingga tahun
2025.
Gambar 1.
Piramida Penduduk Indonesia tahun 2010-2025
Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-202520
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 175
Bentuk piramida yang menggembung di tengah menunjukkan bahwa sejak tahun 2010
jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk
usia non produktif. Menurut Razali Ritonga, sebuah negara dikatakan mengalami bonus demografi
jika dua orang penduduk usia produktif (15-64) menanggung satu orang tidak produktif (kurang
dari 15 tahun dan 65 tahun atau lebih). Hal ini memberikan arti bahwa dengan banyaknya jumlah
penduduk produktif dan sedikitnya jumlah penduduk yang ditanggung, akan memberikan
keuntungan ekonomi bagi Indonesia. Menurut perhitungan, Indonesia sudah mengalami bonus
demografi sejak tahun 2012, dan puncaknya akan terjadi di tahun 2028-2030.21
.
Gambaran kenaikan pevalensi penyakit jantung pada semua umur menurut provinsi dan
berdasarkan pengelompokan umur, dapat dilihat pada gambar.2:
Gambar 2.
(a)Prevalensi Penyakit Jantung (diagnosis dokter) pada penduduk
semua umur menurut provinsi. (b) Prevalensi Penyakit Jantung (diagnosis
dokter) menurut kelompok umur (bawah)
Sumber: Laporan Hasil Riskesdas 2007, 2013 dan 2018
Pada gambar 2. (a) prevalensi penyakit jantung menurut diagnosis dokter dalam sepuluh
tahun (2007-2018) pada penduduk semua umur mengalami peningkatan di tiap provinsi.
Peningkatan prevalensi tertinggi pada tahun 2018 di provinsi Kalimantan Utara sebesar 2.2%, yang
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 176
sebebelumnya di tahun 2007 tertinggi pada provinsi Aceh sebesar 2%. Sedang prevalensi nasional
penyakit jantung menurut diagnosis dokter mengalami kenaikan dari 0.9 % pada tahun 2007
menjadi 1.5% pada tahun 2018. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur (usia produktif) pada
gambar 2.(b), prevalensi penyakit jantung mengalami kenaikan di setiap interval kelompok umur.
Kenaikan tertinggi pada rentang usia produktif (15-64 tahun) terjadi pada kelompok umur dengan
interval 55-64 tahun.
Gambaran proporsi merokok pada penduduk umur ≥ 10 tahun menurut kelompok umur
dapat dilihat pada gambar.3:
Gambar 3.
(a) Proporsi merokok pada penduduk umur ≥ 10 tahun menurut kelompok umur;
(b) Prevalensi merokok pada populasi usia 10-18 tahun, 2018.
Sumber : Laporan Hasil Riskesdas 2013 dan 2018
Pada gambar 3 (a) proporsi merokok pada usia produktif terjadi sedikit peningkatan pada
interval 15-19 tahun (dari 18.3% tanun 2013 menjadi 19.6% tahun 2018) dan 25-29 tahun tahun
(dari 34.8% tanun 2013 menjadi 35.2% tahun 2018). Namun, jika di lihat menurut kelompok umur
secara keseluruhan proporsi merokok pada usia produktif mengalami penurunan. Ini sesuai dengan
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 177
proporsi nasional merokok pada penduduk umur ≥ 10 tahun mengalami penurunan dari 29.3% di
tahun 2013 menjadi 28.8% di tahun 2018. Peningkatan Prevalensi merokok justru terjadi pada
populasi usia 10-18 tahun, ini terlihat pada gambar 3 (b) dimana pada tahun 2013 sebesar 7.2%
menjadi 9.1% pada tahun 2018.
Gambaran proporsi kurang aktivitas fisik (kegiatan kumulatif kurang dari 150 menit
seminggu) pada penduduk umur ≥ 10 tahun menurut provinsi dapat dilihat pada gambar.4:
Gambar 4.
(a) Proporsi aktivitas fisik kurang pada penduduk umur ≥10
tahun menurut provinsi; (b) Proporsi aktivitas fisik kurang
pada menurut kelompok umur
Sumber : Laporan Hasil Riskesdas 2013 dan 2018
Pada gambar 4 (a) proporsi aktivitas fisik kurang pada penduduk usia ≥ 10 tahun mengalami
peningkatan di 27 provinsi pada tahun 2018 di bandingkan denga tahun 2013. Peningkatan proporsi
aktifitas fisik kurang juga terlihat pada angka prevalensi yang di dapatkan pada hasil pengukuran di
tingkat nasional dari 26.1% pada tahun 2013 menjadi 33.5 % pada tahun 2018. Namun, jika di lihat
menurut kelompok umur proporsi aktivitas fisik kurang tertinggi berada pada kelompok usia
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 178
remaja (10-14 tahun) sebesar 64.4%. Sedang pada usia produktif kelompok yang memiliki aktifitas
fisik tinggi adalah kelompok usia 15-19 tahun sebesar 49.6% dan kelompok dengan usia 20-24
tahun sebesar 33.2%.
Proporsi perilaku konsumsi minuman beralkohol dalam 1 bulan terakhir pada penduduk
umur >10 tahun menurut provinsi dan kelopok umur dapat dilihat pada gambar.5:
Gambar 5.
(a) Proporsi perilaku konsumsi minuman beralkohol dalam 1 bulan
terakhir pada penduduk umur ≥10 tahun menurut provinsi; (b)
Proporsi perilaku konsumsi minuman beralkohol dalam 1 bulan
terakhir pada kelompok umur
Sumber : Laporan Hasil Riskesdas 2013 dan 2018
Pada gambar 5 (a) proporsi perilaku konsumsi minuman beralkohol dalam 1 bulan terakhir
pada penduduk usia ≥ 10 tahun mengalami peningkatan di 30 provinsi pada tahun 2018 di
bandingkan denga tahun 2013. Peningkatan proporsi perilaku konsumsi minuman beralkohol juga
terlihat pada angka prevalensi yang di dapatkan pada hasil pengukuran di tingkat nasional dari
3.0% pada tahun 2013 menjadi 3.3 % pada tahun 2018. Namun, jika di lihat menurut kelompok
umur proporsi perilaku konsumsi minuman beralkohol tertinggi berada pada kelompok usia 20-24
tahun sebesar 64.4%.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 179
Proporsi prilaku konsumsi makanan berisiko (≥1 kali per hari) pada penduduk umur ≥10
tahun menurut provinsi dan kelopok umur dapat dilihat pada gambar.6:
Gambar 6.
(b) Proporsi prilaku konsumsi makanan berisiko (≥1 kali per
hari) pada penduduk umur ≥10 tahun di Indonesia; (b)
Proporsi prilaku konsumsi makanan berisiko (≥1 kali per
hari) pada penduduk umur ≥10 tahun menurut kelompok
umur
Sumber : Laporan Hasil Riskesdas 2013 dan 2018
Pada gambar 4 (a) proporsi perilaku konsumsi makanan berisiko (≥1 kali per hari) di tingkat
nasional pada penduduk umur ≥10 tahun mengalami penurunan pada jenis dan makanan olahan,
sedangkan peningkatan terjadi pada jenis makanan asin dan berlemak. Namun, jika di lihat menurut
kelompok umur proporsi perilaku konsumsi makanan berisiko (≥1 kali per hari) pada penduduk
umur ≥10 tahun di tiap jenis makanan berisiko relatif sama.
Prevalensi hipertensi pada penduduk umur ≥18 tahun menurut kelopok umur dapat dilihat
pada gambar.7:
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 180
Gambar 7.
Prevalensi hipertensi pada penduduk umur ≥18 tahun menurut
kelopok umur
Sumber : Laporan Hasil Riskesdas 2013 dan 2018
Pada gambar 7. Tahun 2013, prevalensi hipertensi mengalami kenaikan pada tiap kelompok
umur, nilai prevalensi tertinggi berada pada kelompok umur 65-74 tahun. Pada usia produktif,
kenaikan prevalensi hipertensi terjadi pada interval umur 25-64 tahun. Nilai prevalensi hipertensi
mengalami kenaikan ditingkat nasional, dimana hasil pengukuran tahun 2007 sebesar 7.2%,
menjadi 9.4% di tahun 2013, dan 8.36% di tahun 2018.
Peningkatan Beban Biaya Pengobatan
Penyakit jantung menciptakan beban ekonomi yang cukup tinggi untuk negara, yaitu melalui
pembiayaan kesehatan. Menurut data Jamkesmas penyakit jantung merupakan salah satu penyakit
terbanyak yang dialami oleh pasien rawat jalan dan rawat inap pada tahun 2012. Total biaya yang
dikeluarkanuntuk biaya rawat jalan dan rawat inap di tingkat lanjut sebesar Rp.22.995.073.768.22
Data BPJS menunjukkan adanya peningkatan biaya kesehatan untuk PJK dari tahun ke tahun. Pada
tahun 2014 penyakit jantung menghabiskan dana BPJS Kesehatan sebesar Rp 4,4 triliun, kemudian
meningkat menjadi 7,4 triliun pada 2016, masih terus meningkat pada 2018 sebesar Rp 9,3 triliun.23
Penyakit jantung merupakan penyakit akibat gaya hidup yang salah. Semakin banyak orang terkena
penyakit jantung, tentu membuat beban negara akan semakin semakin tinggi.
PEMBAHASAN
Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, angka kejadian penyakit
jantung dan pembuluh darah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Setidaknya, 15 dari 1000
orang, atau sekitar 2.784.064 individu di Indonesia menderita penyakit jantung.24
Penyakit jantung
merupakan salah satu penyakit yang berpotensi mengurangi keuntungan ekonomi, pada saat
Indonesia diprediksi akan memperoleh bonus demografi yang harusnya bisa dirasakan oleh
Indonesia pada tahun 2020. Jika usia produktif bisa berperan optimal enam tahun mendatang maka
bangsa ini diprediksi akan bisa memperoleh bonus demografi tersebut secara optimal. Namun jika
generasi yang diharapkan tersebut menderita penyakit maka hal ini akan menjadi salah satu faktor
penghambat untuk memperoleh bonus yang diharapkan. Banyak kajian menyimpulkan bahwa
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 181
75%-90% kejadian penyakit jantung disebabkan oleh faktor tradisional yaitu usia, riwayat
keluarga, hipertensi, dyslipidemia, diabetes, kurangnya aktivitas fisik dan obesitas 25
. Rokok, pola
makan dan aktivitas fisik adalah faktor yang diamati pada Riset Kesehatan Dasar dalam 10 tahun
terakhir 19,24,26
.
Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan yang preventif, agar prilaku
merokok dapat di turunkan secara signifikan. Pada profil masyarakat ASEAN tahun 2011, salah
satu keuntungan demografi Indonesia adalah lebih dari 60% penduduk berusia dibawah 39 tahun.
Sementara jika melihat hasil RISKESDAS pada kelompok umur tersebut terpapar salah satu faktor
risiko terkena penyakit jantung yaitu merokok. Menurut penelitian di Banglades perokok aktif lebih
beresiko 1,3 kali di bandingkan mantan perokok. Kematian akibat penyakit jantung meningkat pada
laki-laki dan perempuan. Diestimasikan rokok berkonteribusi terhadap 25% kematian pada laki-
laki dan 7.6% pada perempuan.27
Perokok yang berhenti merokok sebelum usia 37 tahun ririko
terkena penyakit jantung sama dengan yang tidak pernah merokok.
Data Riskesdas menunjukkan bahwa proporsi perokok usia 25-34 tahun masing-masing
sebesar 29% pada tahun 2007 dan 31,1% pada tahun 2013.19,24,26
Terlihat bahwa terjadi peningkatan
proporsi jumlah perokok. Faktor risiko ini berpotensi untuk menyebabkan penyakit jantung pada
usia 40 tahun ke atas. Selain itu juga berisiko untuk menyebabkan kematian akibat penyakit
jantung yang diderita. Sementara, jika perilaku merokok ini bisa dikurangi sebelum usia 37 tahun,
maka risiko untuk menderita penyakit jantung bisa ditekan, karena risiko terkena penyakit jantung
pada mantan perokok yang berhenti sebelum usia 37 tahun sama dengan yang tidak pernah
merokok. Artinya berisiko lebih rendah terkena penyakit jantung.
Selain itu dari aspek pembiayaan kesehatan faktor risiko merokok ini juga akan membenai
belanja Negara pada sektor kesehatan, khususnya untuk biaya pelayanan kesehatan. Pada sisi lain
faktor risiko ini juga akan menimbulkan kerugian dalam bentuk kehilangan produktivitas yang jika
di konversikan secara nominal menunjukkan nilai yang besar. Hal ini bisa dilihat dari hasil
penelitian di Inggris bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan kesehatan akibat merokok
pada tahun 1991 adalah sekitar 1,4-1,7 juta dan telah menyebabkan 100.000 kematian dalam 10
tahun terakhir. Diperkirakan kematian akibat rokok pada tahun 2005 adalah sekitar 109,164 (18%
dari kematian, 27% kematian pada pria dan 11% wanita). Rokok menjadi penyebab 12% dari
kegagalan hidup pada tahun 2002 (15% pada pria dan 8,5% pada wanita) serta membebani biaya
peyanan kesehatan nasional sebesar £5,2 juta pada tahun 2005-2006.28
Jika faktor risiko rokok tidak dikendalikan secepatnya maka bonus demografi akan
mengalami penurunan dari sektor sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan, akibat
meningkatnya prevalensi penyakit jantung dan kerugian ekonomi yang ditimbulkannya. Penelitian
di Amerika terhadap penduduk berkulit hitam menemukan bahwasanya aktifitas fisik yang kurang
berhubungan dengan penyakit jantung, gagal jantung dan penyakit jantung koroner.29
Aktifitas fisik
yang kurang, bisa meningkatkan risiko terkena penyakit jantung pada wanita.30
Suatu studi kohor
menemukan bahwa tingginya porsi kegiatan santai atau duduk berhubungan dengan peningkatan
fatalitas penyakit jantung di bandingkan waktu santai yang sedikit.31
Banyak laporan penelitian
menemukan hubungan antara waktu santai dengan penyakit jantung Lebih jauh lagi di temukan
hubungan antar kebiasaan duduk/sedentary, berhubungan dengan periko kematian akibat penyakit
jantung.32
Berdasarkan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terlihat bahwa aktivitas fisik yang
kurang akan meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Jika proporsi aktivitas fisik didominasi
oleh santai/duduk-duduk, maka itu juga akan meningkatkan faktor risiko penyakit jantung. Jika hal
ini dibiarkan, maka pada saat bonus demografi hal ini juga akan mengurangi produktivitas dan
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 182
kualitas sumberdaya manusia. Hal ini akan mengurangi keuntungan dari bonus demografi yang
seharusnya bisa diperoleh.
Penyakit jantung selain mengurangi kualitas bonus demografi, juga berdampak kepada biaya
penanggulangan. Sebuah penelitian di Inggris menyebutkan bahwa biaya yang diperlukan untuk
system penanganan penyakit jantung pada tahun 2004 adalah sekitar £29,1 juta, 29% (£8,5 juta)
dan 27% (£8.0 juta) dari total biaya. Biaya pelayanan kesehatan adalah bagian terbesar yang
diperlukan untuk penanganan penyakit jantung yaitu sebesar 60%, diikuti oleh biaya yang
ditimbulkan akibat kehilangan produktivitas selama sakit dan kematian sebesar 23% dan 17% biaya
yang dikeluarkan untuk pelayanan informal.33
di Korea biaya yang diperlukan untuk system
penanganan penyakit jantung secara nasional adalah $2,52 juta. Biaya tersebsar dikeluarkan untuk
biaya medis yaitu sebesar 53%, diikuti dengan biaya untuk kehilangan produktivitas selama sakit
dan kematian (33,6%), transportasi (8,1%) dan biaya perawatan lainnya (4,9%).34
Merujuk kepada
biaya yang dikeluarkan oleh kedua negara tersebut di atas, jika dikonversi kepada nilai mata uang
Indonesia maka biaya yang dikeluarkan berkisar antara Rp. 2.936.807.791.705 s/d Rp.
5.620.411.366.865. Inilah biaya yang dikeluarkan jika faktor-faktor risiko Penyakit jantung tidak di
kelola dengan baik.
Kurangnya aktivitas fisik, akan menyebabkan obesitas pada 68% orang dewasa. Biaya yang
ditimbulkan akibat obesitas pada perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat adalah sebesar $225.8
juta per-tahun untuk segala hal yang berhubungan dengan hilangnya produktivitas. Rata-rata biaya
pelayanan kesehatan yang dikeluarkan per-orang mencapai $3,000 per-tahun. Pekerja yang
kegemukan akan menambah biaya pengeluaran perusahaan untuk kesehatan dan sakit per-tahun
antara $460 to $2,500.35
Aktivitas fisik yang mencukupi bisa menurunkan risiko terkena penyakit
jantung.36
Dari beberapa penelitian tersebut terlihat bahwa, biaya yang dikeluarkan akibat
kurangnya aktivitas fisik bisa menambah pengeluaran kesehatan. Hal ini akan menjadi sebuah
konsekuensi yang harus dihadapi dari segi pembiayaan kesehatan pada saat bonus demografi, jika
tidak dilakukan intervensi sedini mungkin.
Salah satu cara yang umum digunakan utuk menurunkan biaya perawatan penderita
penyakit jantung adalah dengan berolahraga secara teratur. Ini bukan sekadar himbuan semata,
melainkan sudah dibuktikan melalui penelitian. Jika penderita penyakit jantung masih takut-takut
atau masih mencari alasan apa pentingnya berolahraga setiap hari, mulai saat ini buang jauh-jauh
keraguan untuk berolahraga. Menurut sebuah penelitian, penderita penyakit jantung yang rutin
melakukan olahraga intensitas sedang selama lebih kurang 30 menit minimal lima kali dalam
seminggu, dapat menghemat biaya berobat sampai 2.500 dolar Amerika, atau hampir 30 juta
rupiah. Penelitian ini sudah dimuat dalam Jurnal American Heart Association.
Yang dimaksud olahraga intensitas sedang adalah olahraga yang menghasilkan sedikit
keringat atau hanya sedikit meningkatkan napas dan detak jantung, misalnya jalan cepat,
memotong rumput, atau bersih-bersih. Bagi yang memiliki kekuatan lebih, bisa meningkatkan
intensitasnya dengan lari, berenang atau aerobic cukup masing-masing 25 menit 3 kali seminggu.
Siapa saja yang direkomendasikan melakukan olahraga rutin? Dalam penelitian ini, mereka
yang mendapatkan manfaat dengan olahraga adalah penderita penyakit kardiovaskular, termasuk
penderita penyakit arteri koroner, stroke, serangan jantung, gangguan irama jantung atau penderita
penyakit arteri perifer. Mereka inilah golongan penderita penyakit yang mengeluarkan biaya cukup
tinggi untuk perawatan sehari-hari.
Pada beberapa artikel ilmiah sudah banyak dinyatakan bahwa tidak ada satupun penyakit
yang tidak mendapatkan manfaat dari olahraga. Hanya karena mengidap penyakit jantung atau
pernah mengalami serangan jantung, tidak berarti sesorang harus diam dan tidak berolahraga sama
sekali. Berikut ini adalah manfaat berolahraga untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 183
Menguatkan otot jantung dan sistem kardiovaskular. Memperbaiki sirkulasi darah dan membantu
tubuh menyerap oksigen lebih baik. Memperbaiki gejala gagal jantung. Menurunkan tekanan darah.
Memperbaiki kadar kolesterol.
KESIMPULAN DAN SARAN
Faktor risiko merokok dan aktifitas fisik kurang pada kelompok usia di bawah 39 tahun jika
tidak dikelola dengan baik, maka bisa diprediksi kejadian penyakit jantung pada tahun 2020 akan
jauh lebih besar. Hal ini akan menimbulkan masalah bukan hanya dalam pembiayaan kesehatan,
akan tetapi juga menimbilkan konsekuensi pada kerugian yang ditimbulkan terganggunya
produktivitas kerja. Perlu dilakukan upaya-upaya prefentif yang optimal untuk menekan resiko
terkena penyakit jantung pada usia produktif. Seperti membuat fasilitas oleh raga di lingkungan
perkantoran; melakukan advokasi tentang bahaya rokok baik di lingkungan kerja, fasilitas umum,
maupun di wilayah pemukiman penduduk.
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih di sampaikan kepada Kepala Badan Litbang Kesehatan, Kepala Pusat
Upaya Kesehatan Masyarakat, yang telah memberikan kemudahan dalam mengakses data Laporan
RISKESDAS tahun 2007, 2013, dan 2018.
DAFTAR PUSTAKA
1. Ross J. Understanding the Demographic Dividend. POLICY Proj. 2004;
2. Adioetomo dan moertiningsih S. Bonus Demografi : Hubungan antara Pertumbuhan
Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi. BKKBN. 2005;
3. Silva JR, Brito J, Akenhead R, Nassis GP. The Transition Period in Soccer: A Window of
Opportunity. Sport Med. 2016;
4. Raharjo Jati W. Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi : Jendela Peluang
Atau Jendela Bencana Di Indonesia ? Populasi. 2015;
5. Win O, Iba Z. Bonus Demografi Modal Membangun Bangsa yang Sehat dan Bermartabat.
Maj Ilm Unimus. 2011;
6. Mendis S, Puska P, Norrving B. Global atlas on cardiovascular disease prevention and
control. World Heal Organ. 2011;
7. Kaptoge S, Pennells L, De Bacquer D, Cooney MT, Kavousi M, Stevens G, et al. World
Health Organization cardiovascular disease risk charts: revised models to estimate risk in 21
global regions. Lancet Glob Heal. 2019;
8. Müller-Nordhorn J, Willich SN. Coronary Heart Disease. In: International Encyclopedia of
Public Health. 2016.
9. Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI). Pedoman Tatalaksana
Gagal Jantung Edisi Pertama. Buku Pedoman Tatalaksana Gagal Jantung. 2015;
10. Reamy B V., Williams PM, Kuckel DP. Prevention of Cardiovascular Disease. Primary
Care - Clinics in Office Practice. 2018.
11. Heart Failure Society of America. Executive Summary: HFSA 2010 Comprehensive Heart
Failure Practice Guideline. J Card Fail. 2010;
12. Maggioni AP. Review of the new ESC guidelines for the pharmacological management of
chronic heart failure. Eur Hear Journal, Suppl. 2005;7(J):15–20.
13. Saler S. Gagal Jantung Kongestif. Kesehat Univ Sumatera Utara. 2013;
14. Djausal AN. Gagal Jantung Kongestif Congestive Heart Failure. J Medula Unila. 2016;
15. Sani A. Seluk beluk gagal jantung kongestif. jakarta; 2007.
16. Alwan A, Armstrong T, Cowan M RL. Non communicable Diseases Country Profiles 2011.
World Heal Organ. 2011;
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 184
17. WHO. Noncommunicable Diseases Country Profiles 2018. World Health Organization.
2018.
18. World Health Organization. Global status report on noncommunicable diseases. World Heal
Organ. 2010;
19. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Laporan Nasional Riskesdas 2007.
Kementeri Kesehat Republik Indones. 2008;
20. Badan Pusat Statistik Indonesia. Indonesia Population Projection 2010-2035. Badan Pusat
Statistik Indonesia. 2013.
21. Mason A. Population change and economic development in East Asia: challenges met,
opportunities seized. Choice Rev Online. 2002;
22. Kemenkes RI. Situasi kesehatan jantung. Pus data dan Inf Kementeri Kesehat RI [Internet].
2014;3. Available from:
http://www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-
jantung.pdf
23. P2PTM Kemenkes RI. Hari Jantung Sedunia (HJS) Tahun 2019 : Jantung Sehat, SDM
Unggul [Internet]. 2019. p. 1. Available from: http://p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-
p2ptm/pusat-/hari-jantung-sedunia-hjs-tahun-2019-jantung-sehat-sdm-unggul
24. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Laporan Riskesdas 2018 [Internet].
Lembaga Penerbit Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan. Jakarta; 2018.
Available from: https://www.litbang.kemkes.go.id/laporan-riset-kesehatan-dasar-riskesdas/
25. Kannel WB, Vasan RS. Adverse Consequences of the 50% Misconception. American
Journal of Cardiology. 2009.
26. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Riset Kesehatan Dasar 2013. Ris Kesehat
Dasar 2013. 2013;
27. Wu F, Chen Y, Parvez F, Segers S, Argos M, Islam T, et al. A Prospective Study of
Tobacco Smoking and Mortality in Bangladesh. PLoS One. 2013;
28. Luengo-Fernández R, Leal J, Gray A, Petersen S, Rayner M. Cost of cardiovascular
diseases in the United Kingdom. Heart. 2006;
29. Bell EJ, Lutsey PL, Windham BG, Folsom AR. Physical activity and cardiovascular disease
in African Americans in atherosclerosis risk in communities. Med Sci Sports Exerc. 2013;
30. Chomistek AK, Manson JE, Stefanick ML, Lu B, Sands-Lincoln M, Going SB, et al.
Relationship of sedentary behavior and physical activity to incident cardiovascular disease:
Results from the women‘s health initiative. J Am Coll Cardiol. 2013;
31. Ford ES, Caspersen CJ. Sedentary behaviour and cardiovascular disease: A review of
prospective studies. Int J Epidemiol. 2012;
32. Shiyovich A, Shlyakhover V, Katz A. Sitting and cardiovascular morbidity and mortality.
Harefuah. 2013.
33. Allender S, Balakrishnan R, Scarborough P, Webster P, Rayner M. The burden of smoking-
related ill health in the UK. Tob Control. 2009;
34. Chang HS, Kim HJ, Nam CM, Lim SJ, Jang YH, Kim S, et al. The socioeconomic burden
of coronary heart disease in Korea. J Prev Med Public Heal. 2012;
35. Darzi Ara BD of DEC. The price of inactivity. Public Finance. 2012.
36. Roohafza H, Khani A, Sadeghi M, Bahonar A, Sarrafzadegan N. Health volunteers‘
knowledge of cardiovascular disease prevention and healthy lifestyle following a
community trial: Isfahan healthy heart program. J Educ Health Promot. 2014;
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 185
STUDI KOHORT : ANALISIS KETAHANAN HIDUP PASIEN
HEMODIALISIS DENGAN KOMORBID HIPERTENSI DI RUMAH SAKIT
ABDOEL MOELEOK, LAMPUNG
Nurhalina Sari,
1* Nova Muhani,
1 Dias Dumaika,
2 Aprizal Hendardi
2
1Departemen Epid dan Biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Malahayati
2Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Malahayati
Jl. Pramuka No.27 Kemiling, Bandar Lampung, Lampung
Corresponding email: [email protected]
KOHORT'S STUDY: SURVIVAL ANALYSIS OF HEMODIALISTIC PATIENTS WITH
HYPERTENSION COMORBIDES AT ABDOEL MOELEOK HOSPITAL, LAMPUNG
ABSTRACT
The presence of hemodialysis patients is one of the consequences of increasing cases of chronic kidney
disease (CKD). Hypertension is one of the main factors that can accelerate the decline in quality of life in
patients with CKD. The aim of the study was to determine the mean and correlation between patient survival
and comorbid hypertension on the death status of hemodialysis patients.This study used a retrospective
cohort study design. The data source comes from the medical record documents of hemodialysis patients at
the Abdoel Moeloek Hospital during 2016-2018. The data collected were 396 people. Data analysis using
Kaplan Meier and Cox regression. The frequency distribution showed that 320 (80.2%) people had
hypertension. The proportion of the hypertensive group who died was 184 (57.5%). The mean of survival in
the hypertensive group was 33 months, while in the non-hypertensive group was 44 months. The cox
regression test results show a p-value of 0.008 and a hazard ratio of 1.6 (95% confidence interval 1.1-2.3).
The mean length of life of CKD patients in the hypertension group was shorter than the non-hypertensive
group. The hypertensive group had a 1.6 times greater survival risk of dying than the non-hypertensive group
with a 95% confidence interval of 1.1-2.3 in hemodialysis patients undergoing hemodialysis. Awareness to
regularly measure blood pressure and perform early detection of hypertension is highly recommended. This
can be done by utilizing the Posbindu (Integrated Service Post) program in Primary Healthcare and
optimizing the socialization of the Germas (Healthy Living Community Movement) program to the public
through various media.
Keywords: Survival Analysis, Hemodialysis, Hypertension.
ABSTRAK
Keberadaan pasien hemodialisis adalah salah satu akibat dari meningkatnya kasus penyakit ginjal kronis
(PGK). Hipertensi menjadi salah satu faktor utama yang bisa mempercepat penurunan kualitas hidup pada
penderita PGK. Tujuan penelitian adalah mengetahui rerata dan hubungan ketahanan hidup pasien dengan
komorbid hipertensi terhadap status kematian pasien hemodialisis. Penelitian menggunakan desain penelitian
kohort retrospektif. Sumber data berasal dari dokumen rekam medis pasien hemodialisis di Rumah Sakit
Abdoel Moeloek selama tahun 2016-2018. Data yang terkumpul sebanyak 396 orang. Analisis data
menggunakan kaplan meier dan regresi cox. Distribusi frekuensi menunjukkan sebanyak 320 (80.2%) orang
yang mengalami hipertensi. Proporsi kelompok hipertensi yang meninggal dunia sebanyak 184 (57.5%)
orang. Rerata ketahanan hidup kelompok hipertensi adalah 33 bulan, sedangkan pada kelompok non-
hipertensi adalah 44 bulan. Hasil uji regresi cox menunjukkan nilai p-value sebesar 0.008 dan hazard rasio
1.6 (95% interval kepercayaan 1.1-2.3). Rerata lama hidup pasien hemodialisis pada kelompok hipertensi
lebih pendek dibandingkan kelompok non-hipertensi. Kelompok hipertensi memiliki risiko ketahanan hidup
1.6 kali lebih besar untuk mengalami kematian dibandingkan kelompok non-hipertensi dengan 95% interval
kepercayaan 1.1-2.3 pada pasien PGK yang menjalani hemodialisis. Kesadaran untuk rutin mengukur
tekanan darah dan melakukan deteksi dini hipertensisangat dianjurkan. Hal ini dapat dilakukan dengan
memanfaatkan program Posbindu (Pos Pelayanan Terpadu) di Puskemas dan mengoptimalkan sosialisasi
program Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) kepada masyarakat melalui berbagai media.
Kata Kunci: Analisis Survival, Hemodialisis, Hipertensi.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 186
PENDAHULUAN
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan perkembangan kasus kesakitan dan
kematian yang diakibatkan oleh Penyakit Ginjal Kronis (PGK) terus meningkat setiap tahunnya.
Dalam laporan the Global Burden of Disease pada tahun 2017 menyebutkan PGK adalah penyebab
kematian yang terus meningkat menjadi urutan ke-15 pada tahun 2017.1 Laporan yang sama
menyebutkan sekitar 2 juta lebih penduduk dunia mendapatkan perawatan dialisis bahkan
menjalani transplantasi ginjal. Saat ini telah tercatat sekitar 10% penduduk di seluruh dunia
mengalami PGK dan jutaan orang meninggal setiap tahun karena ketiadaan akses pengobatan.
Kementerian Kesehatan Indonesia juga melaporkan bahwa dari total populasi Indonesia yang
berjumlah 258 juta jiwa, 73% kematian disebabkan oleh Penyakit Tidak Menular (PTM) dan 27%
diantaranya berisiko mengalami kematian dini. Salah satu penyumbang kematian dari PTM adalah
penyakit ginjal kronik.2
Perkembangan PGK di Indonesia tercatat memiliki prevalensi sebesar 2 persen berdasarkan
laporan Riskesdas 2013.3 PGK ini menimbulkan beban biaya kesehatan tinggi hingga trilyun
rupiah.2 Perhimpunan Nefrologi Indonesia melaporkan bahwa pasien PGK yang melakukan
hemodialisis tercatat hingga tahun 2016 ada sebanyak 25.446 pasien baru dan 52.835 pasien aktif.4
Faktor risiko penyakit ginjal kronik terbanyak adalah hipertensi dan diabetes mellitus.4–7
Berdasarkan laporan rutin yang dipublikasikan oleh Indonesian Renal Registry (IRR) tercatat PGK
dengan penyakit penyerta hipertensi sebesar 50% pada tahun 2016, kemudian naik menjadi 51%
dan stagnan hingga tahun 2018.5–8
Pada Laporan IRR terlihat PGK dengan hipertensi selalu
menduduki peringkat pertama sebagai penyakit penyerta pasien. Beberapa penelitian menyebutkan
bahwa terdapat hubungan hipertensi dengan kejadian PGK pada pasien yang menjalani
hemodialisis.9–11
Semakin lama menderita hipertensi maka risiko untuk PGK semakin besar. Faktor
risiko utama yang akan diteliti adalah riwayat hipertensi dengan faktor pengganggunya adalah
umur dan jenis kelamin. Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, peneliti ingin
mengetahui dan melakukan analisis lebih lanjut dengan studi kohort retrospektif mengenai
ketahanan hidup pasien hemodialisis dengan komorbid hipertensi di Rumah Sakit Abdoel
Moeloek, Lampung Tahun 2016 – 2018.
METODE
Penelitian ini menggunakan desain kohort retrospektif. Populasi penelitian adalah pasien
dengan status PGK yang menjalani hemodialisis di Rumah Sakit Abdoel Moeloek pada 01 Januari
2016 hingga 31 Desember 2018. Besar sampel minimal dihitung menggunakan rumus uji survival
dari Lwanga dan Lemeshow12
. Rumus ini menggunakan nilai kemaknaan 95 persen (α=5 persen),
kekuatan 80 persen (β=20 persen), dan rasio hazard pasien PGK dengan komorbid hipertensi
sebesar 3.02 dari penelitian Ding, et. al13, sehingga didapatkan jumlah minimal responden adalah
13. Sampel penelitian yang berhasil dikumpulkan sebanyak 396 pasien. Kriteria inklusi adalah
pasien terdiagnosis utama PGK, usia >18 tahun, menjalani hemodialisis, memiliki hasil
laboratorium fungsi ginjal (kreatin), dan catatan tekanan darah. Variabel yang diukur dalam
penelitian ini adalah pasien hemodialisis (meninggal dan hidup) tekanan darah yang dibagi menjadi
non-hipertensi (jika hasil ukur sistolik <140 mmHg dan diastolik <90 mmHg) dan hipertensi (jika
hasil ukur sistolik ≥140 mmHg dan diastolik >90 mmHg), jenis kelamin (perempuan dan laki-laki)
dan umur pasien (<50 tahun dan >50 tahun). Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Abdul
Moeloek selama satu tahun pengumpulan data sejak Oktober 2018 hingga Oktober 2019. Analisis
data menggunakan uji survival, yaitu kaplan meier untuk rerata ketahanan hidup pasien
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 187
hemodialisis dan uji regresi cox digunakan untuk memperkirakan nilai rasio hazard (HR) dan 95%
interval kepercayaan (IK).
HASIL
1. Karakteristik Pasien
Pasien hemodialisis didominasi oleh laki-laki sebanyak 56.6%, mengalami hipertensi 80.8%,
dan meninggal 55.8 persen (tabel 1). Rerata usia pasien hemodialisis berusia 51 tahun dengan usia
termuda 19 tahun dan tertua 82 tahun. Pasien hemodialisis ini rerata telah menjalani proses cuci
darah selama 14 bulan dan pasien terlama selama 10.5 tahun/126 bulan.
Tabel 1. Karakteristik Pasien
Variabel Kategori n ( persen)
Jenis kelamin Perempuan Laki-laki
172 (43.4) 224 (56.6)
Usia <50 tahun
≥50 tahun
164 (41.4)
232 (58.6)
Status pasien Hidup Meninggal
175 (44.2) 221 (55.8)
Tekanan darah Non-hipertensi
Hipertensi
76 (19.2)
320 (80.8)
Gambar 1.
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden berdasarkan Kelompok Non-hipertensi dan
Hipertensi
17 22
18 21
12 25
12 25
perempuan laki-laki <50 tahun >50 tahun
Jenis Kelamin Umur
Kelompok Non-hipertensi
hidup meninggal
70 66
61 75
73 111
73 111
perempuan laki-laki <50 tahun >50 tahun
Jenis Kelamin Umur
Kelompok Hipertensi
hidup meninggal
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 188
1. Survival Pasien Hemodialisis dengan Riwayat Hipertensi
Tabel 3. Regresi cox Ketahanan Hidup Pasien Hemodialisis dengan Komorbid Hipertensi
di RS Abdoel Moeloek Tahun 2016-2018
Variabel p-value Hazard rasio 95% Interval Keparcayaan
Terendah Tertinggi
Tekanan darah .008 1.615 1.133 2.301
Gambar 2.
Grafik Ketahanan Hidup Pasien Hemodialisis dengan Komorbid Hipertensi
di RS Abdoel Moeloek Tahun 2016-2018
Bulan
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 189
Proporsi pasien hemodialisis yang memiliki riwayat hipertensi dan kemudian meninggal
berjumlah 184 (57.5 persen) orang. Pada grafik survival diatas terlihat rerata ketahanan hidup
kelompok hipertensi, yaitu 33 bulan lebih pendek dibandingkan dengan kelompok non-hipertensi,
yaitu 44 bulan. Hasil uji log rank (Mantel-Cox) dan omnibus test pada analisis regresi cox
menunjukkan nilai p-value sebesar 0.007 (α=5 persen), nilai ini secara statistik menunjukkan ada
perbedaan survival rate antara kelompok hipertensi dengan non-hipertensi. Kelompok hipertensi
memiliki risiko ketahanan hidup 1.6 kali lebih besar untuk mengalami kematian dibandingkan
kelompok non-hipertensi dengan 95% interval kepercayaan 1.1-2.3 pada pasien hemodialisis.
PEMBAHASAN
Penyakit ginjal kronis (PGK) didefinisikan sebagai proses penurunan progresif fungsi
ginjal yang dapat terjadi dalam beberapa bulan bahkan tahun. Secara fisiologis, penyakit ini adalah
kerusakan ginjal dan/atau hingga penurunan Glomerular Filtration Rate (GFR) dengan nilai kurang
dari 60mL/min/1,73m selama minimal 3 bulan lamanya.14
Laporan terakhir yang dirilis oleh
Registrasi IRR (Indonesian Renal Registry) tahun 20188, diagnosis penyakit utama pasien
hemodialisis di Indonesia berasal dari tiga jenis penyakit, yaitu: gagal ginjal akut (GGA) sebesar 8
persen, gagal ginjal kronik (GGK/PGK) sebesar 90 persen, dan GGA pada PGK sebesar 2 persen.
Adapun untuk penyakit penyertanya didominasi oleh hipertensi (51 persen) dan diabetes mellitus
(21 persen).
Pada penelitian ini dihasilkan bahwa pasien hemodialisis dari kelompok hipertensi yang
meninggal sejumlah 184 (57.5%). Proporsi pasien hemodialisis yang meninggal karena komorbid
hipertensi lebih besar dibandingkan dengan non-hipertensi. Faktor risiko penyakit ginjal kronis di
Indonesia menurut data Riskesdas 2018 adalah hipertensi dengan prevalensi sebesar 25.%, obesitas
15.4%, dan diabetes melitus 2.3%.15
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok hipertensi
memiliki risiko ketahanan hidup 1.6 kali lebih besar untuk mengalami kematian dibandingkan
kelompok non-hipertensi dengan 95% interval kepercayaan 1.1-2.3 pada pasien hemodialisis.
Beberapa laporan nasional juga menyebutkan penyebab kematian tertinggi pada pasien
hemodialisis adalah kardiovaskuler. Faktor risiko penyakit penyerta tertinggi penyakit
kardiovaskuler tersebut adalah hipertensi. Hipertensi masih merupakan komorbid tertinggi. Hal ini
dapat dijelaskan bahwa apapun penyakit dasar yang telah diderita oleh pasien, bila sudah
mengalami PGK dan menjalani hemodialisis maka kontrol tekanan darah pun akan terganggu.2,3,5–8
Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Nurcahyati16
dan Delima, et. al17
menyebutkan bahwa
adanya hubungan signifikan antara tekanan darah dengan kualitas hidup pasien PGK yang
menjalani hemodialisis. Hasil ini diperkuat dari beberapa penelitian yang juga menyatakan bahwa
pasien PGK yang menjalani hemodialisis dengan komorbid hipertensi memiliki ketahanan hidup
lebih rendah jika dibandingkan dengan pasien yang tidak memiliki riwayat penyakit apapun.9,18,19
Peluang risiko ketahanan hidup pasien hemodialisis dengan komorbid hipertensi semakin lama
akan semakin kecil. Menurut teori, penyakit hipertensi yang diderita dalam waktu lama akan
menyebabkan nefrosklerosis, kemudian berlanjut menjadi kerusakan glomerulus dan atrofi tubulus
hingga seluruh nefron rusak dan berdampak pada gagal ginjal.9 Penyakit ginjal kronik dapat
menyebabkan naiknya ukuran tekanan darah, begitu pula sebaliknya hipertensi dalam jangka
waktu lama juga dapat mengganggu fungsi kerja ginjal. Keterbatasan pada penelitian ini adalah
sulit untuk membedakan keadaan anatara hipertensi lebih dulu atau penyakit ginjak kronik dulu
yang terjadi. Keterbatasan informasi pada lembar rekam medis yang tertulis di dalamnya. Pengaruh
hipertensi pada ginjal tergantung dari ukuran tingginya tekanan darah dan lamanya waktu
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 190
menderita hipertensi. Semakin tinggi tekanan darah seseorang dan diderita dalam waktu lama,
maka berakibat pada semakin berat komplikasi penyakit yang mungkin dapat ditimbulkan.
Sejalan dengan hasil penelitian dan laporan nasional IRR menyebutkan bahwa pasien
hemodialisis didominasi oleh jenis kelamin laki-laki pada kisaran angka 56-60%. Penelitian
Sulistiowati dan Idaiani menyebutkan laki-laki memiliki risiko 2.97 kali lebih besar untuk
mengalami PGK.20
Penelitian Pranandari dan Supadmi juga menyatakan hal sama bahwa laki-laki
berisiko hingga 2 kali lebih tinggi untuk menderita PGK (p.value=0.04)21
dan beberapa penelitian
lainnya.22
Namun dalam penelitian lain menunjukkan tidak ada hubungan antara jenis kelamin
terhadap risiko ketahanan hidup pasien PGK.19
Perbedaan hasil penelitian ini disebabkan oleh
beberapa faktor seperti pengaruh perbedaan hormon reproduksi; gaya hidup seperti konsumsi
protein, garam, rokok dan konsumsi alkohol pada laki-laki dan perempuan. Pasien hemodialisis
pada penelitian ini didominasi oleh usia di atas 50 tahun sekitar 58.6%, meski pada data ditemukan
juga usia termuda pasien hemodialisis adalah 19 tahun.
KESIMPULAN DAN SARAN
Rerata lama hidup pasien hemodialisis dari kelompok hipertensi lebih rendah
dibandingkan kelompok non-hipertensi. Pasien hemodilasis dari kelompok hipertensi memiliki
risiko kematian lebih tinggi 1,6 kali jika dibandingkan kelompok non-hipertensi. Peneliti
menyarankan agar individu dan masyarakat memiliki kemadirian dan kesadaran tinggi untuk
melakukan kontrol rutin tekanan darah. Deteksi dini hipertensi sangat dianjurkan dengan
memanfaatkan program posbindu yang ada di puskemas dan mengoptimalkan sosialisasi germas
(Gerakan Hidup Sehat Masyarakat). Bagi mereka yang telah terdiagnosis positif mengalami
hipertensi juga disarankan untuk patuh mengonsumsi obat antihipertensi agar tekanan darahnya
terkontrol dan berupaya mengubah gaya hidup serta mengendalikan stres. Penelitian lanjutan perlu
dilakukan dengan menggunakan data pasien yang lebih akurat terkait status lamanya dan terkontrol
tidaknya hipertensi pasien dan faktor penting lainnya seperti gula darah/diabetes.
DAFTAR PUSTAKA
1. Stanaway JD, Afshin A, Gakidou E, Lim SS, Abate D, Abate KH, et al. Global, regional,
and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and
occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990-
2017: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Stu. Lancet.
2018;392(10159):1923–94.
2. Moeloek NF. Air Bagi Kesehatan : Upaya Peningkatan Promotif Preventif bagi Kesehatan
Ginjal di Indonesia [Internet]. Jakarta; 2018 [cited 2018 Aug 31]. Available from:
https://www.persi.or.id/images/2018/data/materi_menkes.pdf
3. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS)
2013. Laporan Nasional 2013. Jakarta; 2013.
4. Lydia A, Nugroho P. Kondisi Kesehatan Ginjal Masyarakat Indonesia dan
Perkembangannya [Internet]. 2018 [cited 2018 Aug 31]. Available from:
https://www.persi.or.id/images/2018/data/aida_lydia.pdf
5. Indonesian Renal Registry Team. 8 th Report Of Indonesian Renal Registry 2015 [Internet].
2015 [cited 2018 Aug 30]. Available from:
https://www.indonesianrenalregistry.org/data/INDONESIAN RENAL REGISTRY
2015.pdf
6. Indonesia Renal Registry Team. 9 th Report Of Indonesian Renal Registry 2016 [Internet].
2016 [cited 2018 Aug 31]. Available from:
https://www.indonesianrenalregistry.org/data/INDONESIAN RENAL REGISTRY
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 191
2016.pdf
7. Indonesian Renal Registry Team. 10 th Report Of Indonesian Renal Registry 2017
[Internet]. 2017. Available from: https://www.indonesianrenalregistry.org/data/IRR 2017
8. Indonesian Renal Rgistry Team. 11 th Report Of Indonesian Renal Registry 2018 [Internet].
2018. Available from: https://www.indonesianrenalregistry.org/data/IRR 2018.pdf
9. Yulianto D, Basuki H, Widodo. Analisis Ketahanan Hidup Pasien Penyakit Ginjal Kronis
Dengan Hemodialisis Di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. J Manaj Kesehat Yayasan RSDr
Soetomo [Internet]. 2017;3(1):96. Available from:
https://media.neliti.com/media/publications/258424-analisis-ketahanan-hidup-pasien-
penyakit-a82c8244.pdf
10. Hidayati T, Kushadiwijaya H, Suhardi. Hubungan antara Hipertensi, Merokok dan
Minuman Suplemen Energi dan Kejadian Penyakit Ginjal Kronik. Ber Kedokt Masy
[Internet]. 2008;24(2):90–102. Available from:
https://journal.ugm.ac.id/bkm/article/view/3600
11. Fitrianto H, Azmi S, Kadri H. Penggunaan Obat Antihipertensi pada Pasien Hipertensi
Esensial di Poliklinik Ginjal Hipertensi RSUP DR. M. Djamil Tahun 2011. J Kesehat
Andalas [Internet]. 2014;3(1):45–8. Available from: Penggunaan Obat Antihipertensi pada
Pasien Hipertensi Esensial di Poliklinik Ginjal Hipertensi RSUP DR. M. Djamil Tahun
2011
12. Ogston SA, Lemeshow S, Hosmer DW, Klar J, Lwanga SK. Adequacy of Sample Size in
Health Studies. Biometrics. 1991;47(1):347.
13. Ding C, Yang Z, Wang S, Sun F, Zhan S. The associations of metabolic syndrome with
incident hypertension, type 2 diabetes mellitus and chronic kidney disease: a cohort study.
Endocrine [Internet]. 2018;60(2):282–91. Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s12020-
018-1552-1
14. KDIGO. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of
Chronic Kidney Disease. Kidney Int Suppl [Internet]. 2013 [cited 2018 Sep 1];3(1):1–150.
Available from: http://www.kidney-international.org
15. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Hasil Utama Riskesdas 2018. Kementerian
Kesehatan. 2018.
16. Nurcahyati S. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kualitas Hidup Pasien Hemodialisis
di Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dan Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas
[Internet]. Indonesia; 2011. Available from: http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20282431-T
Sofiana Nurchayati.pdf
17. Delima D, Tjitra E, Tana L, Halim FS, Ghani L, Siswoyo H, et al. Faktor Risiko Penyakit
Ginjal Kronik : Studi Kasus Kontrol di Empat Rumah Sakit di Jakarta Tahun 2014. Bul
Penelit Kesehat [Internet]. 2017;45(1):17–26. Available from:
http://ejournal.litbang.kemkes.go.id/index.php/BPK/article/download/7328/5123
18. Pongsibidang GS. Risk Factor Hypertension, Diabetes and Consuming Herbal Medicine of
Chronic Kidney Disease In Dr. Wahidin Sudirohusodo Hospitals Makassar 2015. J Wiyata
[Internet]. 2016;3(2):162–7. Available from:
https://ojs.iik.ac.id/index.php/wiyata/article/view/87
19. Ebad M. Survival analysis of chronic dialysis patients [Internet]. University of Waterloo;
2018 [cited 2018 Aug 31]. Available from: http://hdl.handle.net/10012/13584
20. Eva Sulistiowati, Sri Idaiani. RISK FACTORS OF CHRONIC KIDNEY DISEASE
BASED ON CROSS- SECTIONAL ANALYSIS BASELINE COHORT STUDY NON-
COMMUNICABLE DISEASES AT POPULATION 25-65 YEARS OLD IN KEBON
KELAPA, BOGOR 2011. Bul Penelit Kesehat [Internet]. 2015;43(3):163–72. Available
from: http://ejournal.litbang.kemkes.go.id/index.php/BPK/article/view/4344/4000
21. Pranandari R, Supadmi W. Risk factors cronic renal failure on hemodialysis unit in RSUD
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 192
Wates Kulon Progo. Maj Farm [Internet]. 2015;22(2):316–20. Available from:
https://jurnal.ugm.ac.id/majalahfarmaseutik/article/view/24120/15776
22. Chang PY, Chien LN, Lin YF, Wu MS, Chiu WT, Chiou HY. Risk factors of gender for
renal progression in patients with early chronic kidney disease. Med (United States)
[Internet]. 2016;95(30). Available from: https://journals.lww.com/md-
journal/fulltext/2016/07260/risk_factors_of_gender_for_renal_progression_in.26.aspx
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 193
PEMANFAATAN HASIL STUDI KOHOR
FAKTOR RISIKO PENYAKIT TIDAK MENULAR (FRPTM)
DI KOTA BOGOR 2011—2019
Sulistyowati Tuminah, Woro Riyadina, Sudikno, Dewi Kristanti Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Jl. Percetakan Negara No.29, Jakarta Pusat 10560
Corresponding e-mail: [email protected]
UTILIZATION OF THE RESULTS OF A COHORT STUDY OF
RISK FACTORS FOR NON-COMMUNICABLE DISEASES IN BOGOR CITY (2011—2019)
ABSTRACT
Cerebrovascular disease, ischemic heart disease and diabetes mellitus (DM) are the three leading causes of
death in Indonesia during 2015 and 2016 based on the Sample Registration System (SRS). The results of the
Basic Health Research (BHR) in 2007 showed that the prevalence of stroke, heart disease and diabetes
mellitus in Bogor City were higher than the national prevalence. This is one of the reasons for choosing the
Bogor City as the place for the Non-Communicable Disease Risk Factor (NCDRF) Cohort Study. This study
has been ongoing for 10 years, a lot of data has been produced but it is still not fully utilized. In fact, there
are still many who do not know about this study. The purpose of this paper was to provide information about
the NCDRF Cohort Study with stroke, coronary heart disease (CHD), and DM as the outcomes. For the local
government and the Bogor City health office, the results of the NCDRF Cohort Study are beneficial in
determining priority problems and potential resources. The benefits for the Primary Health Care (PHC)
include obtaining data on health status, morbidity and mortality of residents in their working areas, to
stimulate the formation of the NCD Integrated Founding Post (Posbindu), and improving the skills of health
workers and cadres. Subjects who participated in the NCDRF Cohort Study got the free and routine health
examination. Since 2012—2019 there have been 32 national, 6 international publications and 10 papers
socialyzed through seminars/conferences.
Key words: cohort study, non-communicable disease
ABSTRAK
Penyakit serebrovaskuler, penyakit jantung iskemik dan diabetes melitus (DM) merupakan tiga penyakit
yang menjadi penyebab utama kematian di Indonesia selama tahun 2015 dan 2016 berdasarkan Sample
Registration System (SRS). Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 menunjukkan bahwa
prevalensi stroke, penyakit jantung dan DM di Kota Bogor lebih tinggi dari prevalensi nasional. Hal ini
menjadi salah satu alasan dipilihnya Kota Bogor sebagai tempat pelaksanaan Studi Kohor Faktor Risiko
Penyakit Tidak Menular (FRPTM). Studi ini telah berlangsung selama 10 tahun, banyak data yang dihasilkan
namun masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan masih banyak yang belum mengetahui adanya
kegiatan ini. Tujuan makalah ini yaitu memberikan informasi tentang kegiatan Studi Kohor FRPTM dengan
stroke, penyakit jantung koroner (PJK), dan DM sebagai outcome. Studi Kohor FRPTM yang dimulai sejak
tahun 2011 ini, pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan bekerjasama
dengan berbagai instansi terkait. Bagi pemerintah daerah dan dinas kesehatan Kota Bogor, adanya hasil Studi
Kohor FRPTM memberikan manfaat dalam menentukan prioritas masalah dan sumber daya potensial.
Manfaat bagi PKM yang terlibat antara lain mendapatkan data status kesehatan, morbiditas dan mortalitas
warga di wilayah kerjanya, terbentuknya Pos Pembinaan Terpadu (posbindu) PTM, serta meningkatnya
keterampilan tenaga kesehatan dan kader. Warga yang menjadi sampel Studi Kohor FRPTM mendapat
manfaat berupa pemeriksaan rutin dan gratis. Sejak tahun 2012—2019 telah dihasilkan 32 publikasi nasional,
6 publikasi internasional dan 10 makalah yang disosialisasikan melalui seminar/konferensi.
Kata kunci: studi kohor, penyakit tidak menular
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 194
PENDAHULUAN
Di wilayah Asia Tenggara diperkirakan 62% (8,5 juta) dari seluruh kematian, diakibatkan
oleh Penyakit Tidak Menular (PTM). Sekitar 50% dari kematian tersebut terjadi pada usia di bawah
70 tahun. Empat PTM utama yaitu penyakit kardiovaskuler (PKV), diabetes, kanker dan penyakit
pernafasan kronis berkontribusi terhadap lebih dari 80% kematian premature terkait PTM.
Gangguan mental merupakan penyebab utama kelima dari beban PTM dan seringkali terjadi
dengan empat PTM utama. (Castillo-Carandang, 2020)
Penyakit serebrovaskuler, penyakit jantung iskemik dan diabetes melitus (DM) merupakan
tiga penyakit yang menjadi penyebab utama kematian di Indonesia selama tahun 2015 dan 2016
berdasarkan Sample Registration System (SRS). (Usman Y, 2018) Prediktor utama PTM, dan
lamanya perubahan faktor risiko menjadi PTM diperkirakan sangat bervariasi, tergantung jenis
PTM, jenis dan jumlah faktor risiko baik genetik, perilaku maupun lingkungan, lamanya
keterpaparan faktor risiko, dan derajat/dosis/kadar/frekuensi faktor risiko PTM pada seseorang. Hal
tersebut hanya dapat diketahui dengan pasti melalui penelitian etiologi yang dilakukan secara
longitudinal dengan desain studi kohor. Saat ini, Studi Kohor Faktor Risiko PTM secara
longitudinal masih sangat jarang dilakukan di Indonesia. Penelitian yang pernah dilakukan di
Indonesia dengan desain tersebut, masih dengan jumlah sampel, lama pelaksanaan, dan ruang
lingkup yang terbatas. Oleh karena itu Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (BPPK)
Kementerian Kesehatan RI merasa perlu menyelenggarakan studi ini secara komprehensif. Dengan
tersedianya data longitudinal dari faktor risiko yang dipantau secara prospektif dalam mengamati
kejadian PTM utama dapat dikembangkan berbagai studi intervensi yang lebih khusus untuk
mendapatkan berbagai model upaya pengendalian PTM secara efektif, baik pencegahan maupun
pengobatannya. (Lap SKFRPTM 2018)
Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 menunjukkan, prevalensi diabetes,
stroke, dan penyakit jantung di Kota Bogor lebih tinggi dari prevalensi nasional. Prevalensi
tersebut secara berurutan 1,7%; 0,8% dan 1,2% untuk Kota Bogor; 0,7%; 0,6%; 0,9% untuk
Nasional. Hasil Riskesdas tersebut menjadi salah satu alasan dilakukannya Studi Kohor Faktor
Risiko Penyakit Tidak Menular (FRPTM) di Kota Bogor dan dilaksanakan sejak tahun 2011—
sekarang.
Masalah
1. Kegiatan Studi Kohor FRPTM telah berjalan selama 10 tahun, banyak data dihasilkan
namun belum banyak yang berminat membuat penelitian ―nested‖ ataupun analisis lanjut
dari data studi ini yang hasilnya diharapkan dapat digunakan sebagai acuan oleh para
pemegang program dalam rangka mencegah dan mengendalikan PTM utama.
2. Publikasi artikel hasil Studi Kohor FRPTM juga belum banyak dilakukan serta belum
terkoordinir dengan baik, sehingga dikuatirkan terjadinya salami akibat tidak melakukan
sitasi terhadap artikel-artikel yang sudah lebih dahulu dipublikasi.
Tujuan
1. Memperkenalkan Studi Kohor Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular yang telah dilakukan
selama 10 tahun.
2. Mendukung pemanfaatan hasil-hasil Studi Kohor FRPTM oleh kalangan luas untuk dapat
dijadikan sebagai acuan dilakukannya penelitian-penelitian lebih lanjut yang lebih
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 195
mendalam guna memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat Indonesia ke arah yang lebih
baik.
Pelaksanaan Studi Kohor FRPTM
a. Populasi dan sampel
Studi Kohor FRPTM merupakan studi kohor prospektif terhadap individu di lima kelurahan
di Kecamatan Bogor Tengah (Kelurahan Kebon Kalapa, Babakan Pasar, Babakan, Ciwaringin serta
Panaragan), yang dilakukan milai tahun 2011—sekarang. Populasi adalah penduduk tetap berusia
25—65 tahun (saat studi baseline) di kelurahan terpilih. Inklusi: mereka yang bersedia mengikuti
seluruh kegiatan Studi Kohor FRPTM yang akan berlangsung minimal 10 tahun. Eksklusi: mereka
yang menderita sakit berat, tidak mampu berkomunikasi atau menderita gangguan jiwa.
Pengambilan sampel dilakukan secara ―konsekutif‖ yaitu subyek yang memenuhi syarat,
diikutsertakan menjadi responden sampai jumlah yang diperlukan terpenuhi.
Dalam melaksanakan kegiatan Studi Kohor FRPTM, BPPK bekerjasama dengan Dinas
Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor dan 3 Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) yang wilayah kerjanya
menjadi sampel Studi Kohor FRPTM, yaitu PKM Merdeka (Kel. Kebon Kalapa, Ciwaringin dan
Panaragan), PKM Sempur (Kel. Babakan) dan PKM Belong (Babakan Pasar).
Pada studi baseline dilakukan skrining guna menyeleksi subyek sesuai outcome masing-
masing. Studi baseline ini dilaksanakan dalam 3 tahap (tahun 2011, 2012 dan 2015) karena
keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Jumlah total responden pada studi baseline sebanyak
5690 orang. Partisipasi responden selama 8 tahun pemantauan (2011—2019) digambarkan sebagai
berikut:
Gambar 1. Partisipasi responden Studi Kohor FRPTM selama 8 tahun (Laporan SKFRPTM 2019)
Selama 8 tahun perjalanan Studi Kohor FRPTM, rata-rata responden yang hadir di FU 3—4
bulanan sebanyak 92,4%. Rata-rata responden yang hadir pada FU 2 tahunan (tahun ke-2, tahun ke-
4, tahun ke-6) sebesar 84,6%. Sementara responden yang drop-out (DO) sebanyak 8,9%.
Pengumpulan data yang dilakukan dalam Studi Kohor FRPTM menurut lokasi, frekuensi,
tahun, dan jenis kegiatan dijelaskan pada tabel-tabel berikut ini:
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 196
Tabel 1. Pengumpulan data Studi Kohor FRPTM tahun 2011—2020 menurut lokasi dan
frekuensi pelaksanaan pemantauan (follow up/FU)
Tabel 1 menjelaskan bahwa sampai dengan tahun 2019, responden baseline 2011 telah
memasuki tahun ke-8 dan menjalani FU lengkap 2 tahunan yang ke-4 (FU-24). Untuk responden
baseline 2012 telah memasuki tahun ke-7 yaitu FU-21 di posbindu. Sedangkan untuk responden
baseline 2015 baru memasuki tahun ke-4 dan menjalani FU lengkap 2 tahunan yang ke-2. Di tahun
2020, seluruh kegiatan Studi Kohor FRPTM dihentikan akibat adanya pandemi Covid-19, hanya
dilakukan pengumpulan data online yang merupakan kajian dampak masa pandemi terhadap
kesehatan mental dan pola pencarian pelayanan pengobatan pada responden dengan komorbid
PTM.
Tabel 2. Pengumpulan data Studi Kohor FRPTM menurut tahun pelaksanaan
Tabel 3. Pengumpulan data Studi Kohor FRPTM menurut lokasi dan kegiatannya
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 197
b. Wawancara
Dalam Studi Kohor FRPTM terdapat 2 macam wawancara yang dilakukan menggunakan
kuesioner, yaitu wawancara mengenai kesehatan masyarakat (kesmas) dan gizi. Pada wawancara
kesmas dilakukan pendataan mengenai sosiodemografi, riwayat penyakit responden dan keluarga
responden, dalam hal ini penyakit tidak menular seperti penyakit jantung koroner (PJK), stroke,
diabetes melitus (DM), kanker (payudara dan leher rahim) serta penyakit paru obstruksi kronis
(PPOK) serta gejala-gejala yang dirasakan. Selain itu ditanyakan juga faktor risiko perilaku
(kebiasaan merokok, konsumsi alkohol serta aktivitas fisik) dan non perilaku (gangguan
mental/emosional). Sedangkan data konsumsi (pola dan jenis asupan makanan) diperoleh dari
wawancara menggunakan kuesioner gizi dengan cara Food Frequency Questionnaire (FFQ) dan
Recall Diet 24 jam. Wawancara kesmas dilakukan oleh enumerator lulusan ilmu kesehatan,
sedangkan wawancara gizi dilakukan khusus oleh enumerator lulusan sekolah gizi. Para
enumerator sebelum kegiatan Studi Kohor FRPTM dimulai, telah diberi pelatihan.
c. Pengukuran
Pada saat pengumpulan data di lapangan, dilakukan juga pengukuran tekanan darah (TD)
dan antropometri (berat badan/BB, tinggi badan/TB dan lingkar perut/LP). Pengukuran tekanan
darah dan antropometri di posbindu dilakukan oleh kader, sedangkan pada FU 2 tahunan dilakukan
oleh tenaga kesehatan dari PKM di bawah pengawasan tim Studi Kohor FRPTM. Pengukuran
tekanan darah dilakukan terhadap semua responden. Pengukuran antropometri dilakukan terhadap
semua responden kecuali responden yang sedang hamil.
d. Pemeriksaan laboratorium
Dalam Studi Kohor FRPTM dilakukan pemeriksaan kadar gula dan lipid darah terhadap
semua responden kecuali yang sedang hamil. Kadar gula darah yang diperiksa adalah kadar gula
darah puasa dan 2 jam setelah pembebanan (post prandial). Kadar lipid darah yang diperiksa yaitu
kolesterol total, low-density lipoprotein/LDL, high-density lipoprotein/HDL serta trigliserida.
Sebelum pengambilan darah, responden diminta berpuasa selama 12—14 jam serta tidak
diperkenankan beraktivitas fisik berat.
e. Pemeriksaan
Pada Studi Kohor FRPTM ini dilakukan beberapa pemeriksaan yaitu pemeriksaan
neurologi dan pemeriksaan rekam jantung (Elektrokardiograf/EKG) yang masih dilakukan hingga
kini (tahun 2019). Foto toraks (Rontgen) hanya dilakukan sejak tahun 2011—2016. Sedangkan
pemeriksaan payudara (Sadanis dan USG), pemeriksaan leher rahim (IVA) serta pemeriksaan
fungsi paru (Spirometri) hanya dilaksanakan saat baseline 2011 dan 2012.
e.1. Pemeriksaan neurologi
Pemeriksaan neurologi dilakukan terhadap responden yang memiliki gejala stroke atau
pernah stroke menggunakan formulir yang telah disiapkan, ditambah instrumen MMSE dan
MoCA-Ina. Pemeriksaan neurologi dilakukan oleh dokter spesialis syaraf dari RSUPN Cipto
Mangunkusumo.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 198
e.2. Pemeriksaan payudara
Pemeriksaan payudara secara klinis (Sadanis) dilakukan terhadap semua responden
perempuan, kecuali yang sedang hamil atau menyusui ≤6 bulan. Pemeriksaan dilakukan oleh para
perawat yang telah diberi pelatihan oleh dokter spesialis bedah onkologi dari RS Dharmais.
Sedangkan pemeriksaan payudara menggunakan USG dilakukan terhadap responden perempuan
berusia ≥40 tahun atau <40 tahun dengan hasil Sadanis Positif. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter
spesialis radiologi dari RS Dharmais.
e.3. Pemeriksaan leher rahim
Pemeriksaan leher rahim dilakukan dengan metode inspeksi visual dengan asam asetat (IVA)
terhadap responden perempuan yang sudah/pernah melakukan hubungan seksual. Pemeriksaan IVA
dilakukan oleh para bidan yang telah diberi pelatihan oleh dokter spesialis onkologi ginekologi dari
RSUPN Cipto Mangunkusumo.
e.4. Pemeriksaan rekam jantung
Pemeriksaan rekam jantung dilakukan menggunakan elektrokardiograf (EKG) dengan kode
Minnesota. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap responden berusia ≥40 tahun atau <40 tahun yang
mempunyai riwayat penyakit jantung dan atau hipertensi. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas dari
laboratorium klinik swasta yang hasilnya kemudian dikonfirmasikan kepada 2 orang Profesor
spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah dari RS Pusat Jantung Nasional Harapan Kita.
e.5. Pemeriksaan fungsi paru
Pemeriksaan ini dilakukan terhadap responden berusia ≥40 tahun. Pemeriksaan dilakukan
menggunakan spirometri oleh para dokter residen di bidang paru yang selalu diawasi secara
bergantian oleh para Profesor spesialis Paru.
e.6. Pemeriksaan Toraks
Dilakukan terhadap semua responden kecuali responden yang hamil, menggunakan alat
mobile Rontgen (foto toraks/bagian dada). Pengambilan foto toraks dan pembacaan hasil dilakukan
oleh pihak swasta.
f. Pengolahan data
Data hasil wawancara, pengukuran dan pemeriksaan diinput di bawah pengawasan tim
manajemen data Studi Kohor FRPTM. Setelah itu dilakukan cleaning data sebelum dianalisis oleh
tim Studi Kohor FRPTM. Dalam proses analisis data biasanya tim Studi Kohor FRPTM
berkonsultasi dengan pakar statistik.
HASIL STUDI KOHOR FRPTM
1. Laporan rutin
Laporan dikerjakan bersama-sama oleh tim Studi Kohor FRPTM, dengan membagi data
menjadi beberapa blok yaitu blok PJK, DM, Stroke, Hipertensi dan Sindroma Metabolik (SM).
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 199
Laporan diserahkan ke kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat di
Jakarta, Dinkes Kota Bogor, serta PKM yang terlibat dalam kegiatan Studi Kohor ini.
2. Laporan hasil pemeriksaan
Di akhir kegiatan FU 2 tahunan, tim Studi Kohor mengumpulkan dan merekapitulasi hasil
pemeriksaan kesehatan tiap-tiap responden yang selanjutnya dikirimkan melalui PKM yang terlibat
dalam kegiatan Studi Kohor FRPTM yang kemudian akan didistribusikan oleh para kader posbindu
masing-masing.
3. Publikasi
Semua anggota tim Studi Kohor FRPTM diberikan kesempatan untuk menulis artikel
menggunakan data hasil kegiatan ini. Dalam rangka menjaga agar tidak saling tumpang tindih,
maka setiap anggota yang akan menggunakan data Studi Kohor FRPTM terlebih dahulu
menuliskan perkiraan judul tulisan yang akan dibuat, ke dalam buku besar. Bagi orang dari luar
BPPK yang berminat untuk menggunakan data Studi Kohor FRPTM, terlebih dahulu harus
mengajukan proposal yang ditujukan kepada Kepala BPPK dan Kepala Laboratorium Manajemen
Data serta berkoordinasi dengan Ketua Pelaksana.
4. Diseminasi hasil-hasil Studi Kohor FRPTM
Sejauh ini, hasil-hasil Studi Kohor FRPTM belum secara luas didiseminasikan, hanya berupa
artikel-artikel dalam jurnal ilmiah. Baru pada tahun 2018, hasil-hasil Studi Kohor FRPTM
disajikan pada beberapa Konferensi Ilmiah seperti 9th
National Public Health Conference di
Malaysia, The International Epidemiological Association-South East Asia (IEASEA) ke-13 di Bali,
International Conference on Pharmaceutical Updates (ICPU) di Yogyakarta baik berupa presentasi
oral maupun poster.
MANFAAT HASIL STUDI KOHOR FRPTM
1. Hasil Studi Kohor FRPTM yang dilakukan selama 10 tahun telah memberikan manfaat bagi
Kemenkes, Pemerintah Kota Bogor dan PKM yang terlibat yang disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 4. Manfaat Hasil Studi Kohor Faktor Risiko PTM bagi Kemenkes dan Pemda
Kota Bogor dan PKM
*Sumber: Buku ―Rekam jejak Studi Kohor FRPTM‖
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 200
2. Kader posbindu
Meningkatnya ketrampilan para kader dalam melakukan pengukuran tekanan darah dan
antropometri serta penggunaan aplikasi (hp) dalam menghitung indeks massa tubuh (IMT)
responden. Memberikan pengalaman baru dalam penggunaan aplikasi online untuk pelaporan
morbiditas dan mortalitas responden.
3. Responden
Responden diperiksa kesehatannya secara berkala dan tidak dipungut biaya, sehingga
terpantau kondisi kesehatannya. Mendapatkan hasil pemeriksaan kesehatan yang jika hasilnya
tidak normal, dapat ditindak lanjuti oleh PKM atau dirujuk ke RS di Kota Bogor.
4. Peneliti dan Mahasiswa
Sejak tahun 2012—2019 tim Studi Kohor FRPTM telah menghasilkan 32 publikasi di
jurnal nasional, 6 publikasi di jurnal internasional dan 10 makalah yang dipublikasikan melalui
seminar/konferensi. Selain itu juga ada beberapa permintaa data Studi Kohor FRPTM dari luar
BPPK untuk tesis maupun disertasi. Berikut ini disajikan judul-judul publikasi/permintaan data
Studi Kohor FRPTM.
Tabel 5. Output yang dihasilkan Studi Kohor FRPTM sejak tahun 2012—2019
* Sumber: Buku Rekam Jejak Studi Kohor FRPTM
Layanan permintaan data hasil riset
BPPK memiliki unit Laboratorium Manajemen Data yang bertugas mengelola raw data
hasil penelitian dari satuan kerja di lingkungan BPPK baik yang dilakukan perorangan maupun
hasil penelitian skala besar, yaitu Survei Kesehatan Nasional (Surkesnas), Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas), Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes), Studi Diet Total dan lain-lain.
Prosedur permohonan, persyaratan penggunaan data-data, biaya dan lain-lain, dapat dilihat
pada website berikut ini:
https://www.litbang.kemkes.go.id/layanan-permintaan-data-riset/
atau https://labmandat.litbang.kemkes.go.id/menu-layan
Untuk mengakses laporan hasil riset Badan Litbang Kesehatan dapat dilihat pada website:
https://labmandat.litbang.kemkes.go.id/
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 201
Tabel 6. Judul publikasi di jurnal nasional yang menggunakan data Studi Kohor FRPTM
No Judul Penulis Nama Jurnal Tahun
1 Determinan DM Analisis
Baseline Data Studi Kohor PTM
2011.
Olwin Nainggolan Buletin Penelitian Sistem
Kesehatan Vol. 16 N0 3,
Juli 2013
2013
2 Faktor risiko dan komorbiditas
migraine.
Woro Riyadina,
Yuda Turana.
Bulletin Penelitian Sistem
Kesehatan 2014, 17(4):
371-378.
2014
3 Stress as a major determinant of
migraine in women aged 25—65
years.
Woro Riyadina,
Lelly Andayasari.
Universa Medicina 2014,
33(2): 142-150.
2014
4 Faktor risiko tumor payudara
pada perempuan umur 25—65
tahun di lima kelurahan
Kecamatan Bogor Tengah.
Marice Sihombing,
April Nur Sapardin.
Jurnal Kesehatan
Reproduksi. Vol. 5 No. 3
Desember 2014; 175-184.
ISSN: 2087-703X.
2014
5 Hubungan konsumsi kopi
terhadap strok atau penyakit
jantung koroner (Baseline data
studi kohor faktor risiko
penyakit tidak menular).
Sulistyowati
Tuminah dan Woro
Riyadina.
Gizi Indonesia 2014,
37(1):29-40.
2014
6 Sindrom Metabolik Pada Orang
Dewasa di Kota Bogor, 2011-
2012.
Anna Maria Sirait,
Eva Sulistiowati.
Media Litbangkes 2014;
24(2):81-88.
2014
7 Penyakit Jantung Koroner [PJK]
dengan Obesitas di Kelurahan
Kebon Kalapa, Bogor [Baseline
Studi Kohor Faktor Risiko
PTM].
Rustika dan Ratih
Oemiati.
Bulletin Penelitian Sistem
Kesehatan 2014;
17(4):385-393
2014
8 Pengetahuan tentang Faktor
Risiko, Perilaku dan Deteksi
Dini Kanker Serviks dengan
Inspeksi Visual Asam Asetat
(IVA) pada Wanita di
Kecamatan Bogor Tengah, Kota
Bogor.
Eva Sulistiowati,
Anna Maria Sirait.
Buletin Penelitian
Kesehatan Vol. 42. No.3,
September 2014. Hal 193-
202.
2014
9 Faktor Risiko Penyakit Ginjal
Kronik berdasarkan Analisis
Cross Sectional Data Awal Studi
Kohor penyakit Tidak menular
Penduduk Usia 25-65 tahun di
Kelurahan Kebon Kalapa Kota
Bogor Tahun 2011.
Eva Sulistiowati, Sri
Idaiani
Buletin Penelitian
Kesehatan Vol. 43. No.3,
September 2015. Hal 163-
172.
2015
10 Frequent coconut milk intake
increases the risk of vascular
disease in adults.
Sulistyowati
Tuminah, Marice
Sihombing.
Universa Medicina May-
August 2015; 34(2):149-
159. pISSN: 1907-
3062/eISSN: 2407-2230.
2015
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 202
11 Hubungan komponen sindrom
metabolik dengan risiko
Diabetes Melitus tipe 2 di
lima kelurahan Kecamatan
Bogor Tengah.
Marice Sihombing,
Sulistyowati Tuminah.
Media Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan,
2015; 25(4):219—226.
ISSN: 0853—9987.
2015
12 Faktor risiko sindrom
metabolik pada orang
dewasa di Kota Bogor.
Marice Sihombing,
Hapsari Dwi
Tjandrarini.
Jurnal Penelitian gizi dan
makanan. Vol. 38 No. 1
Juni 2015; 21-
30. ISSN: 0125-9717.
2015
13 Gambaran Kohor 2011-2013
Gangguan Mental Emosional
Berdasarkan SRQ-20 pada
Penduduk Kelurahan Kebon
Kalapa Bogor.
Sri Idaiani, Aprildah
Nur Sapardin, Eva
Sulistiowati.
Buletin Penelitian
Kesehatan, Vol. 43, No. 4,
Desember 2015: 273-278.
2015
14 Gender, family income, and
the risk of mental emotional
disorders in selected
population.
Sri Idaiani, Aprildah
Nur Sapardin, Eva
Sulistiowati.
Health Science Journal of
Indonesia. Vol. 6 No. 1
Juni 2015. Page 23-28.
ISSN: 2087-7021
2015
15 Insiden dan Faktor Risiko
Diabetes Melitus pada Orang
Dewasa di Kota Bogor.
Anna Maria Sirait,
Eva Sulistiowati,
Marice Sihombing,
Arya Kusuma, Sri
Idaiani.
Bulletin Penelitian Sistem
Kesehatan. 2015:
18(2):151-160
2015
16 Faktor Risiko Penyakit
Jantung Koroner (PJK) pada
Perempuan (Baseline Studi
Kohor Faktor Risiko PTM).
Ratih Oemiati,
Rustika.
Buletin Penenlitian Sistem
Kesehatan 2015; 18(1):47-
55
2015
17 Survival Rate penyandang
hipertensi dengan konsumsi
natrium rendah terhadap
kejadian stroke.
Ekowati Rahajeng,
dan Woro Riyadina.
Gizi Indonesia 2016,
39(2):71-80.
2016
18 Perbedaan Laju Kecepatan
Terjadinya Hipertensi
Menurut Konsumsi Natrium
(Studi Kohort Prospektif di
Kota Bogor Jawa Barat,
Indonesia).
Ekowati Rahajeng,
Dewi Kristanti, Nunik
Kusumawardani.
Journal Penelitian Gizi
dan Makanan, Vol 39 No
1 tahun 2016. DOI
10.22435/pgm.v39i1.5972.
45-53.
2016
19 NCEP-ATP III and IDF
criteria for metabolic
syndrome predict type 2
diabetes mellitus.
Eva Sulistiowati,
Marice Sihombing.
Universa Medicina. Vol
35 No.1, January-April
2016. 46-55.
2016
20 Karakteristik peminum
alkohol, Studi Kohor PTM.
Ratih Oemiati dan
Dewi Kristanti
Majalah Kedokteran UKI 2016
21 Sensitifitas dan spesifisitas
pertanyaan gejala saluran
pernapasan dan faktor risiko
untuk kejadian PPOK.
Lusianawaty Tana Buletin Penelitian
Kesehatan Vol 44 No 4
tahun 2016
2016
22 Faktor Risiko Penyakit Tidak Sri Idaiani, Eva Cermin Dunia 2017
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 203
Menular pada Responden
yang diindikasikan Stroke
Berdasarkan Penelitian
Kohort Penyakit Tidak
Menular Bogor 2011-2013.
Sulistiowati, Aprildah
Nur Sapardin.
Kedokteran. CDK-249,
vol. 44 no. 2 th. 2017.
23 Determinan obesitas pada
perempuan pasca menopause
di Kota Bogor tahun 2014.
Woro Riyadina,
Nasrin Kodim dan
Madanijah S.
Gizi Indonesia 2017,
40(1):45-58.
2017
24 Trigliserida sebagai faktor
prognosis untuk hipertensi
tidak terkendali pada wanita
pasca menopause di Kota
Bogor, Tahun 2014.
Woro Riyadina W,
Nasrin Kodim,
Krisnawati Bantas,
Trihandini, Sartika
RAD, E Martha, Yuda
Turana, Ekowati
Rahajeng
Jurnal Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan
2017, 45(2):89-96.
2017
25 Faktor Determinan Penyakit
Jantung Koroner pada
Kelompok Umur 25-65 tahun
di Kota Bogor, Data Kohor
2011-2012.
Julianty Pradono, Asri
Werdhasari.
Buletin Penelitian
Kesehatan, Vol.46, No. 1,
Maret 2018: 23–34
2018
26 Perilaku Berisiko dan
Keluhan Subjektif Memori
(KSM) pada Kelompok Umur
25 Tahun ke Atas di Kota
Bogor Tengah.
Julianty Pradono Media Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan,
vol. 28, no. 2, Juni, 2018:
103-112
2018
27 Obesity Risk Factors among
25-65 Years Old Adults in
Bogor City, Indonesia: A
Prospective Cohort Study.
Sudikno, Hidayat
Syarief, Cesilia Meti
Dwiriani, Hadi Riyadi,
Julianty Pradono.
Jurnal Gizi dan Pangan
Vol 13, No 2, Juli 2018:
55-62.
2018
28 Obesitas Sentral pada Orang
Dewasa : Studi Kohor
Prospektif di Kota Bogor.
Sudikno, Woro
Riyadina, Ekowati
Rahajeng.
Jurnal Gizi Indonesia. Vol
1, No 2, September 2018:
105-116.
2018
29 Perilaku Pencegahan dan
Pengendalian Hipertensi:
Studi Pengetahuan, Sikap,
Perilaku (PSP) dak Kesehatan
Lingkungan pada Wanita
pasca menopause di Kota
Bogor.
Woro Riyadina, Evi
Martha, Athena
Anwar.
Jurnal Ekologi Kesehatan
2018.
2018
30 Perkembangan Diabetes
Melitus Tipe 2 dari
Prediabetes di Bogor, Jawa
Barat.
Eva Sulistiowati,
Marice Sihombing.
Jurnal Penelitian dan
Pengembangan Pelayanan
Kesehatan. Vol 2 No. 1,
April 2018. Hal 59-69.
2018
31 Hormonal contraception
increases risk of breast tumor
based on clinical breast
examination among adult
women.
Sulistyowati Tuminah,
Aprildah Nur Sapardin
Jurnal Universa Medicina.
Vol.36 No.2
May-August 2017. Hal:
139—149.
2017
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 204
32 High carbohydrate intake
increases risk of coronary
heart disease in adults: A
prospective cohort study.
Sulistyowati Tuminah,
Tri Wahyuningsih,
Sudikno
Jurnal Universa Medicina.
Vol.38 No.2 May-August
2019. Hal: 72—81.
2019
Tabel 7. Judul publikasi di jurnal internasional yang menggunakan data Studi Kohor FRPTM
No Judul Penulis Nama Jurnal Tahun
1 The Relationship of Obesity
Index and Lipid Profile in 25—
65 years old Adults in Bogor
City (Baseline Data of Cohort
Study on Non-Communicable
Disease in Bogor City, West Java
Province)
Sudikno, Syarief H,
Dwiriani CM,
Riyadi H, Julianty
Pradono
International Journal
of Sciences Basic and
Applied Research
2017
2 Controlled hypertension: a
prospective cohort study in
Bogor 2011-2016.
Julianty Pradono,
Woro Riyadina,
Dewi Kristanti,
Yuda Turana.
BMC public Health
(proses review ke 2)
2018
Incidence and Risk Factors of
Subjective Memory Complaints
in Women in Central Bogor City,
Indonesia.
Julianty Pradono,
Sudikno, Ika
Suswanti, Yuda
Turana.
Journal of Clinical
Gorontology (proses
review ke 2)
2018
4 Viceral adiposy index and lipid
accumulation product as a
predictor of type 2 Dabetes
Mellitus: The Bogor cohort study
of Non-communicable Disease
Risk Factors.
Dicky Tahapary,
Pradana, Woro
Riyadina, et al.
Diabetes Research and
Clinical Practice
(proses review)
2018
5 Hypertension as the main
predictor of stroke in the adult
population age 25 years and
above: a prospective cohort study
for 6 years in Bogor, Indonesia.
Woro Riyadina,
Julianty Pradono,
Dewi Kristanti,
Yuda Turana.
Journal of
Cardiovascular
Disease Research
(submitted)
2019
6 Hypertension in postmenopausal
women: The Pattern of weight
cycling decreased in bood
pressure.
Woro Riyadina, et
al.
MJI (submitted) 2019
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 205
Tabel 8. Judul makalah yang menggunakan data Studi Kohor FRPTM
dan disajikan dalam seminar/konferensi
No Judul Penulis Nama seminar/
conference
Tempat dan
Waktu
kegiatan
1 Determinan Penyakit Stroke
Pada Masyarakat di
Kelurahan Kebon Kalapa –
Bogor.
Tim kohor PTM Disajikan dalam acara
Simposium Regional I
(SIMREG)
Yogyakarta, 9-
12 Oktober 2012
2 Incidence Rates and Risk
Faktors of Diabetes
Mellitus, Coronary Heart
Disease, Stroke in District
of Central Bogor, West Java
Province. Cohort Study.
Pradono J, Woro
Riyadina.
Simposium Regional
Penelitian dan
Pengembangan
Kesehatan
Jakarta, 17-20
Nopember 2014.
3 The role of Lifestyle on
non-communicable disease
profile in Indonesia:
Evidence from
epidemiology study.
Julianty Pradono Jakarta Diabetes
Meeting 25 tahun.
Jakarta, 12
Nopember 2016.
4 The Hazard Ratio of Stroke
in Adult Population 25 years
and Above: A Perspective
Cohort Study 2011-2017 in
Bogor, Indonesia.
Woro Riyadina,
Julianty Pradono,
Dewi Kristanti.
9th National Public
Health Conference
Malaysia, 15-18
Juli 2018.
5 Controlled hypertension: a
prospective cohort study in
Bogor 2011-2016.
Julianty Pradono 13th IEA SEA
Meeting and ICPH –
Sdev
Bali, 2 Oktober
2018.
6 Risk factors of dyslipidemia
in adults: A cohort study
Sudikno, Julianty
Pradono
13th IEA SEA
Meeting and ICPH –
Sdev
Bali, 2 Oktober
2018.
7 Woman is higher risk
having metabolic syndrome
than man: A prospective
cohort study during 6 years
in Bogor, Indonesia
Srilaning Driyah,
Ratih Oemiati,
Nova Sri Hartati
13th IEA SEA
Meeting and ICPH –
Sdev
Bali, 2 Oktober
2018.
8 Risk Factors and Hazard
Rate of Diabetes Mellitus
Type 2 In A Cohort Study
of A Non-Communicable
Disease in Bogor.
Eva Sulistiowati,
Marice Sihombing.
13th IEA SEA
Meeting and ICPH –
Sdev
Bali, 2-5
Oktober 2018.
9 Predictors of Coronary
Heart Disease (CHD)
among adults (During six
years of Cohort Study on
The Risk Factors of Non-
Communicable Disease).
Sulistyowati
Tuminah Darjoko,
Tri Wahyuningsih,
Sudikno, Aprildah
Nur Sapardin
13th IEA SEA
Meeting and ICPH –
Sdev
Bali, 2-5
Oktober 2018
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 206
10 Hormonal contraception
increases risk of breast
tumor based on clinical
breast examination among
adult women (Baseline of
The Cohort Study on The
Risk Factors of Non-
Communicable Diseases).
Sulistyowati
Tuminah Darjoko,
Aprildah Nur
Sapardin.
International
Conference on
Pharmaceutical
Update (ICPU)
Yogyakarta, 17-
19 OKtober
2018
Tabel 9. Permintaan data Studi Kohor FRPTM untuk skripsi, tesis, disertasi, analisis lanjut
No Judul Instansi pengusul Tahun Kepentingan
1 Gambaran aktivitas fisik, asupan makan
dan kegemukan pada insiden PJK pada
laki-laki dan perempuan usia 25-44 tahun
di Bogor
UHAMKA 2016 Skripsi
2 Studi longitudinal faktor risiko non klinis
dan pengembangan hipertensi di Indonesia
(2011-2016)
Sekolah Tinggi
Farmasi Bandung
2017 Skripsi
3 Faktor yang mempengaruhi DM terkontrol
dan tidak terkontrol dari Studi Kohor
FRPTM tahun 2011 – 2016
FKM-UI 2017 Skripsi
4 Hubungan asupan serat dan LDL
FKM-UI 2012 Tesis
5 Analisis lanjut baseline data Kohort PTM
hubungan perokok pasif dengan asma
FKM-UI 2014 Tesis
6 Hubungan obesitas dengan asma
FKM-UI 2014 Tesis
7 Pengaruh status menopause terhadap PJK
FKM-UI 2014 Tesis
8 Hubungan DM dengan kejadian PJK
FKM-UI 2016 Tesis
9 Hubungan obesitas dengan hipertensi pada
orang dewasa (2011-2016)
FKM-UI 2017 Tesis
10 Analisis ketahanan (survival) terhadap
kejadian stroke pada penduduk dengan
status SM dan non SM yang dipengaruhi
usia, status merokok, aktivitas fisik dan
asupan berserat (2011-2016)
FKM-UI 2017 Tesis
11 Hubungan pola konsumsi sayur, buah dan
makanan berisiko dengan obesitas sentral
pada wanita usia 25-65 tahun di Bogor
FKM-UI 2017 Tesis
12 Hubungan DM dengan fungsi kognitif
FKM-UI 2017 Tesis
13 Hubungan stadium klinik penderita kanker
paru dengan ketahanan hidup kanker paru
FKM-UI 2017 Tesis
14 Hubungan kebiasaan merokok terhadap
kejadian PPOK (baseline 2011)
FKM-UI 2017 Tesis
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 207
15 hubungan DM tipe 2 dengan gangguan
fungsi paru
FKM-UI 2017 Tesis
16 Hubungan pengetahuan dengan perilaku
deteksi dini kanker serviks pada wanita di
Kelurahan Kebon Kalapa Kota Bogor
FKM-UI 2017 Tesis
17 Pengaruh aktivitas fisik terhadap kadar
gula darah penderita DM tipe 2 (2011-
2016)
FKM-UI 2018 Tesis
18 Pengaruh durasi obesitas menurut ABSI
terhadap kejadian DM tipe 2 (2011-2017)
FKM-UI 2018 Tesis
19 Hubungan gangguan tidur dengan
kejadian PJK baseline 2011)
FKM-UI 2018 Tesis
20 Hubungan stress dengan kejadian PJK
(baseline 2011)
FKM-UI 2018 Tesis
21 Stress dan konversi prediabetes menjadi
DM tipe 2 pada orang dewasa di Kota
Bogor
FKM-UI 2018 Tesis
22 Model prediksi risiko kardiovaskular pada
dewasa berusia 40-65 tahun
UGM 2019 Tesis
23 Perbedaan insidensi penyakit jantung
koroner pada pasien diabetes yang
mengkonsumsi obat oral diabetes dan
injeksi insulin: studi kohor Bogor
2011/2012 - 2015/2016
Fakultas Farmasi UI 2019 Tesis
24 Kualitas diet dan kejadian Diabetes
Melitus tipe 2 di Kota Bogor
Gizi IPB 2019 Tesis
25 Faktor risiko penyakit kardiovaskuler
pada orang dewasa umur 25-65 tahun
Gizi IPB 2019 Tesis
26 Faktor risiko diet dan non diet terhadap
kejadian sindrom metabolikpada orang
dewasa
Gizi IPB 2019 Tesis
27 Faktor risiko komplikasi obesitas pada
penderita hipertensi di usia dewasa hingga
lansia (25-65 tahun)
FKM-UI 2019 Tesis
28 Pengaruh konsumsi daging merah, daging
putih, produk olahannya dan makanan
berpengawet terhadap hipertensi pada usia
25-65 tahun (studi kohor faktor risiko
PTM tahun 2015, 2016 dan 2017)
FKM-UI 2019 Tesis
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 208
29 Faktor risiko obesitas pada penderita
daibaetes mellitus usia 25-65 tahun (studi
kohor faktor risiko PTM tahun 2015, 2016
dan 2017)
FKM-UI 2019 Tesis
30 Rasio LDL terhadap HDL dengan
kejadian stroke pada penduduk dewasa di
kota Bogor
FKM-UI 2019 Tesis
31 Hubungan antara perilaku merokok
dengan kejadian DM tipe 2 di Kecamatan
Bogor Tengah tahun 2011 – 2017
FKM-UI 2019 Tesis
32 Risiko Hipertensi Tidak Terkontrol dan
Peningkatan IMT (Analisis data
longitudinal 2011 – 2018)
FKM-UI 2019 Tesis
33 Perilaku makan dan dyslipidemia pada
penyandang diabetes di kecamatan Bogor
Tengah.
FKM-UI 2016 Disertasi
34 Faktor-faktor yang mempengaruhi
konversi prediabetes pada wanita.
FKM-UI 2017 Disertasi
35 Dinamika perubahan indeks massa tubuh
dan tekanan darah pada wanita pasca
menopause, tahun 2011/2012 –
2014/2015.
FKM-UI 2017 Disertasi
36 Faktor risiko obesitas dan dyslipidemia
pada orang dewasa di Kota Bogor.
IPB 2017 Disertasi
37 Insulin resistance risk score development
using dietary and non dietary indicators:
An approach to type 2 DM prevention
Program Gizi FK-UI 2019 Disertasi
38 Komponen Sindrom Metabolik sebagai
prediktor kualitas hidup terkait kesehatan
(Health Related Quality of Life) pada
orang dewasa di Kec. Bogor Tengah, Kota
Bogor
FKM-UI 2019 Disertasi
39 Status obesitas terhadap survival time
prediabetes di Kota Bogor tahun 2011 –
2018.
FKM-UI 2019 Disertasi
40 Hubungan kebiasaan konsumsi makanan
sumber lemak trans dengan profil lipid
darah masyarakat Bogor usia 25-60 tahun
FKM-UI 2019 Disertasi
41 Perbandingan kadar leptin pada individu
dengan TGT dan DM di Bogor tahun
2011 dan 2013
Puslitbang Biomedis 2015 Analisis lanjut
42 Persentase polimorfisme gen ADRB3
pada derajat obesitas penderita DM
Puslitbang Biomedis 2017 Analisis lanjut
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 209
43 Studi longitudinal hipertensi Sekolah Tinggi
Farmasi Bandung
2018 Analisis lanjut
44 Diet DASHI terhadap perubahan tekanan
darah pada penderita hipertensi
FKM-UI 2019 Analisis lanjut
Kesimpulan:
Studi Kohor FRPTM masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Masih diperlukan studi
intervensi yang menindaklanjuti hasil-hasil dari Studi Kohor FRPTM ini.
Daftar Pustaka
1. Castillo-Carandang NT, Buenaventura RD, Chia YC, Van DD, Lee C, et al. Moving towards
optimized non-communicable disease management in the ASEAN Region: Recommendations
from a review and multidisciplinary expert panel. Risk Management and Healthcare Policy.
2020;13: 803—819.
2. Usman Y, Iriawan RW, Rosita T, Lusiana M, Kosen S, et al. Indonesia‘s Sample Registration
System in 2018: A Work in progress. Journal of Population and Social Studies. Volume 27
Number 1, January 2019: 39 – 52 DOI: 10.25133/JPSSv27n1.003.
3. Riyadina W, Sudikno, Pradono J, Rahajeng E, Sirait AM, et al. Laporan Akhir Penelitian Studi
Kohor Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular dan Tumbuh Kembang Anak. Badan Penelitian
dan Pengembangan Kesehatan – Kementerian Kesehatan RI. 2018.
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
Tahun 2007 - Provinsi Jawa Barat. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan –
Kementerian Kesehatan. Jakarta. 2008.
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas) Tahun 2007. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan – Kementerian
Kesehatan. Jakarta. 2008.
6. Riyadina W, Sudikno, Pradono J, Rahajeng E, Sirait AM, et al. Laporan Akhir Penelitian Studi
Kohor Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular dan Tumbuh Kembang Anak. Badan Penelitian
dan Pengembangan Kesehatan – Kementerian Kesehatan RI. Jakarta. 2019.
7. Riyadina W, Rahajeng E, Pradono J, Tuminah S, Kristanti D, et al. Rekam Jejak Studi Kohor
Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Di Kota Bogor. UI Publishing. Jakarta. 2020.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 210
PERAN GEJALA DEPRESI TERHADAP KEJADIAN PENYAKIT TIDAK
MENULAR PADA POPULASI UMUM TAHUN 2007-2014
Rofingatul Mubasyiroh
*, Tri Wuriastuti
1Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat, Balitbangkes, Kemenkes
Jl. Percetakan Negara No. 29, Jakarta Pusat
Corresponding email: [email protected]
THE ROLE OF DEPRESSION SYMPTOMS ON NON-COMMUNICABLE DISEASES IN
GENERAL POPULATION 2007-2014
ABSTRACT
Several studies have shown that non-communicable diseases (NCD) are associated with the incidence and
death from COVID-19. NCD prevalens in Indonesia are increasing year by year. On the other hand, mental
health is a public health issue that contributes to the burden of disease. This study aims to determine the role
of depressive symptoms in the incidence of NCDin the general population. Methods: This study is a further
analysis of Indonesian Family Life Survey (IFLS) data in 2007 and 2014. The sample is population aged 45
years and above in 2014, totaling 7,347 individuals, namely the same individuals in 2007 and 2014. The
dependent variable is diabetes, asthma, chronic lung disease, based on the results of diagnosis by health
professionals reported by respondents. The independent variable was depressive symptoms experienced in
2007. The analysis only involved (inclusion) samples who did not experience diabetes, asthma, chronic lung
disease before or during 2007 data collection. Control variables included were gender, age, education. ,
marital status, occupation, physical activity, smoking, body mass index, residence. Data were analyzed using
multivariate logistic regression. Results: The analysis showed that depressive symptoms played a role in the
incidence of diabetes (aOR=1.75;CI=1.11-2.75), incidence of asthma (aOR=1.83;CI=0.99-3.37), disease
incidence. chronic lungs (aOR=2.26;CI=1.22-4.18). Conclusion: depressive symptoms are associated with
an increased likelihood of diabetes, asthma, and chronic lung disease. Management of mental disorders
should be done before a severe condition, by involving attention to physical health and health behavior.
Keywords: depressive symptoms, NCD, diabetes, asthma, chronic lung disease
ABSTRAK
Latar belakang: Beberapa studi telah menunjukkan penyakit tidak menular (PTM) berhubungan dengan
kejadian dan kematian akibat COVID-19. Kondisi PTM di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke
tahun. Di sisi lain, kesehatan mental menjadi isu masalah kesehatan masyarakat yang berkontribusi pada
beban penyakit. Studi ini bertujuan megetahui peran kondisi gejala depresi terhadap kejadian PTM pada
populasi umum.
Metode: Studi ini merupakan analisis lanjut data Indonesian Family Life Survey (IFLS) tahun 2007 dan
2014. Sampel adalah penduduk usia 45 tahun ke atas pada tahun 2014 yang berjumlah 7.347 individu, yaitu
individu yang sama pada tahun 2007dan 2014. Variabel dependen adalah diabetes, asma, penyakit paru-paru
kronis, berdasarkan hasil diagnosis tenaga kesehatan yang dilaporkan oleh responden. Variabel independen
adalah gejala depresi yang dialami pada tahun 2007. Analisis hanya melibatkan (inklusi) sampel yang tidak
mengalami gangguan diabetes, asma, penyakit paru-paru kronis sebelum atau saat pengumpulan data tahun
2007. Variabel kontrol yang disertakan adalah jenis kelamin, umur, pendidikan, status kawin, pekerjaan,
aktivitas fisik, merokok, indeks massa tubuh, wilayah tempat tinggal. Data dianalisis menggunakan
multivariat regresi logistik.
Hasil: Analisis menunjukkan gejala depresi berperan pada kejadian diabetes (aOR=1,75;CI=1,11-2,75),
kejadian asma (aOR=1,83;CI=0,99-3,37), kejadian penyakit paru-paru kronik (aOR=2,26;CI=1,22-4,18).
Kesimpulan: gejala depresi berhubungan dengan peningkatan peluang kejadian diabetes, asma, penyakit
paru-paru kronik. Penanganan gangguan mental sebaiknya dilakukan sebelum kondisi yang parah, dengan
melibatkan perhatian pada kesehatan fisik dan perilaku kesehatan.
Kata Kunci: gejala depresi, PTM, diabetes, asma, penyakit paru kronik
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 211
PENDAHULUAN
Penyakit Coronavirus-19 (COVID-19) merupakan penyakit menular disebabkan virus
Coronavirus2 (SARS-CoV-2) menyebabkan sindrom pernafasan parah akut yang bisa terjadi
dengan cepat.1 Saat ini telah lebih dari 35 juta penduduk dunia menderita COVID-19, dengan lebih
dari satu juta kematian telah dilaporkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).2 Beberapa kajian
klinis terbaru menunjukkan tingginya jumlah kasus parah dan kematian pada penderita COVID-19
yang memiliki komorbid penyakit tidak menular.3 Analisis dari para penderita COVID-19 di
beberapa negara juga menunjukkan hubungan penyakit tidak menular dengan penumonia dan
kematian akibat COVID.1,4
Beberapa penelitian menyebutkan rata-rata usia penderita COVID-19 dengan comorbid
adalah 46-49 tahun. Dengan beberapa jenis comorbid yang dimiliki oleh penderita COVID-19
adalah asma,Penyakit paru kronis, ginjal, penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi.1,3
Seperti
dilaporkan di Meksiko,bahwa 47,4% dari 212.801 penderita COVID-19 memiliki minimal satu
comorbid PTM.5 Sistematik review menunjukkan diabetes berkaitan dengan keparahan COVID-
19. Kejadian diabetes lebih banyak terjadi pada kelompok yang tidak selamat dari COVID-19.6
Yang juga ditemukan di Meksiko, bahwa komorbid PTM meningkatkan keparahan infeksi COVID-
19.5
Penyakit tidak menular saat ini menyebabkan lebih banyak kematian daripada gabungan
semua penyebab lainnya. Kematian akibat PTM diproyeksikan meningkat dari 38 juta pada tahun
2012 menjadi 52 juta pada tahun 2030, dengan 82% kematian akibat PTM tersebut disebabkan oleh
empat PTM utama (jantung,kanker, penyakit paru kronik dan diabetes). Penyakit paru (termasuk
asma dan paru kronik) penyebab 10,7% dan diabetes penyebab 4% penyebab kematian akibat
PTM.7 Ada kecenderungan peningkatan prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia dari tahun
ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari data Riset Kesehatan Dasar dari tahun 2007, 2013 dan 2018.
prevalensi diabetes menurut diagnosis tenaga kesehatan meningkat dari 0,%7 pada 2007 menjadi
1,5% pada tahun 2013 dan 2018. Pada asma, prevalensi dari 1,9% pada tahun 2007 menjadi 4,5%
pada tahun 2013 dan 2,4% pada 2018. Prevalensi penyakit paru obstruktif kronis hanya
ditunjukkan pada tahun 2013 yaitu sebesar 3,7% dari penduduk usia 30 tahun ke atas.8-10
Orang yang mengalami gangguan mental memiliki risiko lebih tinggi untuk menderita
gangguan fisik tertentu11
,bahkan kematian dini.12,13
Mekanisme hubungan gangguan mental
dengan kondisi penyakit fisik mungkin dapat terjadi melalui penjelasan biologi, perilaku, efek obat
yang dikonsumsi dan juga kurangnya layanan kesehatan. Ada juga mekanisme lain yang perlu
diiungkap seperti genetik dan pola makan.11,12
Bedasarkan sistematik review 17 negara, diperoleh
hasil bahwa gangguan depresi (mood disorder) meningkatkan risiko terjadinya diabetes (aOR=1,3),
asma (aOR=1,3) dan penyakit paru kronik (aOR=1,7).11
Gangguan mental di dunia sudah menjadi hal yang umum. Tiap tahun terdapat satu dari lima
orang di dunia yang terpengaruh akibat masalah ini. Gangguan neuropsikiatri diperkirakan
berkontribusi 13% dari beban penyakit global.14
Depresi adalah salah satu ―common mental
disorder‖, yang prevalensinya tinggi di masyarakat dengan perkiraan jumlah penderitanya di dunia
sebanyak 300 juta penduduk, atau sekitar 4,4% dari total penduduk dunia. Gangguan depresi
ditandai dengan kesedihan, kehilangan minat atau kesenangan, perasaan bersalah atau rendah diri,
gangguan tidur atau nafsu makan, perasaan lelah, dan konsentrasi yang buruk. Depresi bisa
berlangsung lama atau berulang, secara substansial mengganggu kemampuan seseorang untuk
berfungsi di tempat kerja atau sekolah atau menghadapi kehidupan sehari-hari. Depresi yang paling
parah dapat menyebabkan bunuh diri.15
Data gangguan mental di Indonesia secara nasional coba
digambarkan dalam Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yaitu berupa gangguan mental emosional
yang digali menggunakan instrumen SRQ-20, yaitu sebesar 11,6% pada tahun 2007, 6% pada 2013
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 212
dan menjadi 9,8% pada 2013. Sedangkan pada tahun 2018 diukur gangguan depresi menggunakan
instrumen Mini International Neuropsychiatric Interview, diperoleh prevalensi 6% gangguan
depresi pada penduduk usia 15 tahun ke atas.8-10
Banyak hasil penelitian crosssectional yang telah membuktikan hubungan gangguan mental
dengan penyakit tidak menular. Idealnya, hubungan gangguan mental dengan penyakit tidak
menular dilakukan dengan disain kohort untuk melihat pengaruh gangguan mental terhadap
kejadian penyakit tidak menular. Studi ini berupaya mengetahui bagaimana peran kondisi gejala
depresi terhadap kejadian penyakit tidak menular pada seseorang menggunakan disain retrospektif.
METODE
Penelitian ini adalah analisis lanjut data Indonesian Family Life Survey (IFLS). Survei IFLS
dan segala prosedurnya terkait subjek penelitian, telah lolos dari tinjauan IRB (Institutional Review
Boards) di Amerika (oleh RAND di USA) dan di Indonesia oleh Universitas Gajah Mada. IFLS
merupakan survei longitudinal yang dimulai sejak tahun 1993 yang dilajutkan tahun 1997, 2000,
2007, dan 2014. Survei dilaksanakan di 13 provinsi terpilih di Indonesia dengan responden
individu dalam rumah tangga yang terpilih.16
Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur
dan pengukuran. Data IFLS merupakan data yang disediakan untuk umum (publik).
Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data individu pada IFLS ke-empat dan ke-
lima, yaitu dilaksanakan pada tahun 2007 dan 2014. Populasi penelitian adalah individu yang sama
pada tahun 2007 dan 2014, dengan usia 45 tahun ke atas pada tahun 2014. Sampel yang dianalisis
adalah individu yang berusia 45 tahun ke atas yang tidak mengalami diagnosis PTM (diabetes,
asma, penyakit paru kronik) pada sebelum atau saat wawancara survei tahun 2007. Hal ini
dilakukan untuk meningkatkan ketepatan analisis pengaruh independen utama terhadap dependen.
Analisis dilakukan pada sejumlah 7.347 sampel. Responden yang lengkap variabel untuk analisis
asma berjumlah 7.160. Responden yang lengkap variabel untuk analisis penyakit paru lainnya
berjumlah 7.233. Sedangkan responden yang lengkap variabel untuk analisis asma berjumlah
7.160. Responden yang lengkap variabel untuk analisis diabetes berjumlah 6.411.
Variabel Dependen
Variabel dependen yang dianalisis adalah kejadian PTM yang dialami responden selama
kurun waktu setelah tanggal wawancara tahun 2007 hingga tahun 2014. Kondisi PTM digali
menurut pengakuan responden berdasarkan hasil wawancara. PTM yang dimaksud adalah diabetes,
asma, dan penyakit paru-paru kronik lainnya. Responden dikategorikan menderita diabetes jika
sedang mengkonsumsi obat diabetes atau pernah didiagnosis menderita diabetes oleh tenaga
kesehatan. Responden dikategorikan menderita asma jika pernah didiagnosis menderita asma oleh
tenaga kesehatan. Responden dikategorikan menderita penyakit paru-paru kronik lainnya jika
pernah didiagnosis menderita penyakit paru-paru kronik lainnya oleh tenaga kesehatan. Dalam data
IFLS terdapat variabel waktu/kapan pertama kali didiagnosis menderita penyakit, sehingga dalam
analisis hanya dipilih responden yang menderita penyakit setelah tanggal wawancara survei tahun
2007.
Variabel Independen
Variabel independen utama yang dianalisis adalah kondisi gangguan gejala depresi.
Informasi gangguan gejala depresi diperoleh dari instrumen CES-D dari blok KP buku 3 section
3B. Instrumen CES-D ditanyakan pada responden usia 15 tahun ke atas yang terdiri dari 10
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 213
pertanyaan seberapa sering kondisi kesehatan mental yang dialami responden dalam satu minggu
terakhir. Setiap item pertanyaan terdiri dari 4 jawaban, yaitu 1) Rarely or none (≤1 day), 2) Some
days (1-2 days), 3) Occasionally (3-4 days), 4) Most of the time (5-7 days). Setiap jawaban akan
diberikan skor sesuai ketentuan penggunaan instrumen CES-D. Khusus pada petanyaan nomor 5
dan 8, skor tertinggi (nilai 3) adalah pada jawaban berkode 1 (Rarely or none ). Dan pada
pertanyaan lainnya, skor tertinggi (nilai 3) adalah pada jawaban berkode 4(Most of the time). Skor
setiap pertanyaan akan dijumlahkan, dan batas skor 10 ke atas akan dikategorikan menjadi kondisi
depresi.17
Kondisi gejala depresi yang dianalisis adalah kondisi yang dialami pada tahun 2007.
Variabel kontrol
Variabel lain yang dilibatkan dalam analisis di tingkat individu dan rumah tangga di tahun
2007 dan tahun 2014. Yang terdiri dari: jenis kelamin; usia; status kawin; tingkat pendidikan yang
terakhir dicapai; pekerjaan; aktivitas fisik; merokok; indeks massa tubuh (IMT) dan variabel di
tingkat rumah tangga terdiri dari : tipe wilayah tempat tinggal. Variabel-variabel demografi
diperoleh dari buku K section AR. Aktivitas fisik diperoleh dari buku 3B section KK tentang waktu
yang dgunakan untuk berbagai macam kegiatan fisik, baik untuk pekerjaan, untuk aktifitas/kegiatan
sehari-hari di rumah, dan untuk waktu luang seperti rekreasi dan berolahraga dalam 7 hari terakhir,
yang terdiri dari data secara kualitatif (jawaban ―ya‖ dan ―tidak pernah‖) untuk aktivitas fisik berat
(kegiatan yang membuat bernafas jauh lebih berat dari biasanya, seperti mengangkat barang berat,
menggali, mencangkul, bersepeda sambil membawa beban berat, dan sebagainya), aktivitas sedang
(kegiatan yang membuat bernafas agak lebih berat dari biasanya, seperti mengangkat barang yang
tidak terlalu berat, bersepeda dalam kecepatan biasa, atau mengepel lantai (tidak termasuk berjalan
kaki), dan aktivitas jalan kaki (termasuk berjalan kaki di pekerjaan, di rumah, atau dari satu tempat
ke tempat lain. Ini termasuk juga pada saat berekreasi, olahraga, atau di waktu luang). Kebiasaan
merokok diperoleh dari buku 3B section KM, baik pada masa saat survei ataupun masa lalu. Indeks
massa tubuh diperoleh dari data pengukuran berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) di buku US.
IMT dihitung dari BB/(TB dalam meter)2.
Data Analisis
Analisis data dilakukan secara deskriptif univariat, bivariat dan multivariat. Gambaran
kondisi responden menurut demografi, perilaku dan kondisi gejala depresi ditampilkan menurut
distribusi secara univariat (tabel 1). Analisis bivariat untuk memberikan gambaran tentang sebaran
serta hubungan variabel penyakit tidak menular dengan karakteristik dan gejala depresi (Tabel 2).
Multivariat logistik regresi dilakukan untuk menghitung besar peluang kondisi gejala depresi
terhadap penyakit tidak menular setelah dikontrol variabel demografi dan perilaku (Tabel 3). Data
dianalisis menggunakan software SPSS.
HASIL PENELITIAN
Karakteristik responden
Sejumlah 7.347 responden terlibat dalam analisis ini. Responden perempuan (53,5%) sedikit
lebih banyak dari laki-laki (46,5%). Pada tahun 2014, sebagian besar responden pada kelompok
umur 45-64 tahun (78,9%). Rata-rata usia keseluruhan responden saat tahun 2014 adalah 58 tahun.
Status kawin responden sebagian besar kawin/tinggal bersama,baik pada tahun 2007 maupun 2014,
meski terjadi pergeseran persentase pada kelompok yang bercerai (hidup/mati) yaitu dari 14,1%
menjadi 21,6%. Tingkat pendidikan didominasi kelompok pendidikan rendah/ <=SD, baik pada
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 214
2007 dan 2014. Sebagian besar responden bekerja, baik pada tahun 2007 maupun 2014,meski
status bekerja menjadi berkurang pada tahun 2014 (62,0%) dari tahun 2007 (72,4%). Lebih dari
setengah responden tidak pernah merokok, baik tahun 2007 dan 2014. Dengan jumlah mantan
perokok bertambah pada 2014 (8,4%) yang sebelumnya hanya 3,6%. Pada tahun 2007, sebagian
besar responden biasa beraktivitas sedang (49,6%), namun perubahan terjadi pada tahun 2014,
dimana sebagian besar responden tidak biasa beraktivitas (42,3%). Gejala depresi meningkat dari
tahun 2007 (5,3%) ke tahun 2014 (17,4%). Pola tipe wilayah tempat tinggal responden juga terjadi
perubahan, yaitu lebih banyak di perdesaan pada 2007 (51,5%), namun berubah menjadi lebih
banyak yang tinggal di perkotaan pada tahun 2014 (56,1%).
Tabel 1.
Distribusi Responden menurut Karakteristik pada Tahun 2007 dan 2014
Tahun 2007 Tahun 2014
Karakteristik n % n %
Jenis Kelamin - Laki – laki 3419 46,5 3419 46,5
- Perempuan 3928 53,5 3928 53,5
Kelompok Umur - <45 tahun 2020 27,5 0 0
- 45-64 tahun 4644 63,2 5796 78,9
- 65+ tahun 683 9,3 1551 21,1
Status kawin - Kawin/tinggal
bersama
6209 84,5 5679 77,3
- belum kawin 99 1,3 82 1,1
- berpisah/cerai 1039 14,1 1586 21,6
Pendidikan - SMA+ 665 9,1 737 10,0
- SMP 1199 16,3 1219 16,6
- <=SD 5483 74,6 5391 73,4
Status Bekerja - Bekerja 5316 72,4 4552 62,0
- Tidak bekerja 2028 27,6 2795 38,0
Kebiasaan
merokok
- Tidak pernah 4523 61,6 4341 59,1
- Mantan perokok 266 3,6 619 8,4
- Saat ini merokok 2558 34,8 2387 32,5
Aktivitas Fisik - Aktivitas Berat 2528 34,4 1432 19,5
- Aktivitas sedang 3645 49,6 2806 38,2
- Tidak aktivitas 1174 16,0 3109 42,3
Gejala Depresi - Tidak 6957 94,7 6072 82,6
- Ya 390 5,3 1275 17,4
Wilayah tempat
tinggal
- Perkotaan 3564 48,5 4125 56,1
- Perdesaan 3783 51,5 3222 43,9
Total 7.347 100 7.347 100
Secara keseluruhan proporsi kejadian diabetes pada responden usia 45 tahun ke atas adalah
4,4%, kejadian asma adalah 3,0% dan kejadian penyakit paru kronis lainnya adalah 2,0% (gambar
1).
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 215
Gambar 1.
Proporsi Kejadian PTM pada Penduduk Usia 45 tahun ke Atas
Distribusi kejadian PTM berdasarkan beberapa faktor dapat dilihat pada tabel 2. Kejadian
diabetes lebih tinggi pada responden dengan usia 45-64 tahun, pendidikan SMAkeatas, yang
bekerja, riwayat mentan perokok, tidak biasa aktivitas fisik, IMT lebih, riwayat depresi, dan tinggal
di wilayah perkotaan. Kejadian asma lebih banyak diderita oleh kelompok usia 65 tahun ke atas,
tidak bekerja, riwayat mantan merokok, dan riwayat gejala depresi. Kejadian penyakit paru kronik
lainnya banyak dialami oleh responden mantan perokok, riwayat gejala depresi, dan wilayah
tempat tinggal di perkotaan.
Tabel 2.
Hubungan Beberapa Faktor Demografi dan Perilaku dengan Penyakit Tidak Menular
Diabetes
(N=6.411)
Asma
(N=7.160)
Penyakit paru
kronik lainnya
(N=7.233)
Karakteristik n % p-
value
n % p-
value
n % p-
value
Jenis Kelamin - Laki – laki 121 4,1 0,314 61 1,8 0,471 60 1,8 0,208
- Perempuan 162 4,7 79 2,1 55 1,4
Kelompok
Umur
- 45-64 tahun 236 4,7 0,021 95 1,7 0,001 93 1,6 0,637
- 65+ tahun 47 3,3 45 3,0 22 1,5
Status kawin
2014
- Kawin/tinggal
bersama
232 4,7 0,102 111 2,0 0,805 87 1,6 0,773
- belum kawin 1 1,4 1 1,3 2 2,5
- berpisah/cerai 50 3,6 28 1,8 26 1,7
Pendidikan
2014
- SMA+ 52 8,8 0,000 13 1,8 0,895 16 2,2 0,196
- SMP 54 5,4 22 1,8 14 1,2
- <=SD 177 3,7 105 2,0 85 1,6
Status Bekerja
2014
- Bekerja 142 3,6 0,000 73 1,6 0,013 63 1,4 0,102
- Tidak bekerja 141 5,7 67 2,5 52 1,9
Diabetes
Asma
Penyakit paru kronis
95,6
97,0
98,0
4,4
3,0
2,0
Proporsi Kejadian Penyakit Menular pada Penduduk Usia 45 tahun ke Atas (%)
Tidak Ya
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 216
Kebiasaan
merokok 2014
- Tidak pernah 190 5,0 0,000 76 1,8 0,000 67 1,6 0,000
- Mantan perokok 37 6,9 28 4,7 21 3,5
- Saat ini merokok 56 2,7 36 1,5 27 1,1
Aktivitas Fisik
2014
- Aktivitas Berat 30 2,4 0,001 25 1,8 0,165 21 1,5 0,705
- Aktivitas sedang 113 4,7 45 1,6 41 1,5
- Tidak aktivitas 140 5,1 70 2,3 53 1,7
Kategori IMT
2014
- Normal 145 3,5 0,000 119 2,9 0,717 85 1,8 0,090
- BB lebih 56 6,6 27 3,2 13 1,3
- Obesitas 82 5,9 45 3,2 17 1,1
Status kawin
2007
- Kawin/tinggal
bersama
246 4,5 0,443 121 1,0 0,731 94 1,5 0,691
- belum kawin 2 2,4 1 1,0 2 2,1
- berpisah/cerai 35 3,9 18 1,8 19 1,9
Status bekerja
2007
- Bekerja 196 4,3 0,306 85 1,6 0,001 90 1,7 0,159
- Tidak bekerja 87 4,8 55 2,8 25 1,3
Aktivitas Fisik
2007
- Aktivitas Berat 67 3,0 0,000 41 1,7 0,407 35 1,4 0,654
- Aktivitas sedang 163 5,1 75 2,1 61 1,7
- Tidak aktivitas 53 5,3 24 2,1 19 1,7
Kebiasaan
merokok 2007
- Tidak pernah 197 5,0 0,007 86 2,0 0,868 69 1,5 0,319
- Mantan perokok 13 5,7 6 2,4 7 2,8
- Saat ini merokok 73 3,3 48 1,9 39 1,5
Gejala Depresi
2007
- Tidak 260 4,3 0,013 128 1,9 0,066 103 1,5 0,011
- Ya 23 7,2 12 3,2 12 3,2
Wilayah
tempat tinggal
- Perkotaan 208 5,9 0,000 73 1,8 0,360 79 1,9 0,006
- Perdesaan 75 2,6 67 2,1 36 1,1
Tabel 3 menyajikan hasil multivariat regresi logistik pengaruh gejala depresi yang dialami
responden terhadap kejadian penyakit tidak menular yang dikontrol dengan beberapa variabel
demografi dan perilaku. Hasil analisis menunjukkan gejala depresi yang dialami berpengaruh
terhadap kejadian diabetes, dimana orang yang mengalami depresi berpeluang 1,75 kali mengalami
diabetes (aOR=1,75; 95% CI=1,11-2,75). Orang yang mengalami depresi juga berpeluang 1,83 kali
untuk mengalami asma (aOR=1,83; 95%CI=0,99-3,37) dibanding responden yang tidak depresi.
Juga berpeluang 2,25 kali lebih besar untuk mengalami penyakit paru kronik lainnya (aOR=2,25;
95%CI=1,22-4,18) dibandingkan orang yang tidak depresi.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 217
Tabel 3.
Regresi Logistik Gejala Depresi dengan Kejadian Penyakit Tidak Menular
Diabetes
Asma
Penyakit paru kronik lainnya
aOR 95% CI Sig.
aOR 95% CI Sig.
aOR 95% CI Sig.
Depresi Tidak 1
1
1
Ya 1,75 1,11 - 2,75 0,016
1,83 0,99 - 3,37 0,054
2,25 1,22 - 4,18 0,010
Jenis Kelamin Laki-laki 1
1
1
Perempuan 0,79 0,53 - 1,17 0,239
1,54 0,85 - 2,78 0,151
0,63 0,35 - 1,17 0,142
Kelompok Umur 45-64 tahun 1
1
1
65+ tahun 0,69 0,48 - 0,97 0,035
1,65 1,09 - 2,48 0,018
0,64 0,39 - 1,08 0,094
Wilayah tempat tinggal Perkotaan 1
1
1
Perdesaan 0,53 0,40 - 0,71 0,000
1,31 0,91 - 1,87 0,147
0,56 0,37 - 0,85 0,007
Status kawin 2014 Kawin/tinggal bersama 1
0,192
1
0,622
1
0,997
Belum kawin 1,48 0,92 - 2,37 0,105
1,36 0,73 - 2,52 0,330
1,03 0,52 - 2,03 0,943
Cerai 0,42 0,02 - 7,56 0,558
. 0,00 - . 0,999
0,00 - . 0,999
Pendidikan SMA+ 1
0,002
1
0,999
1
0,148
SMP 1,87 1,32 - 2,65 0,000
1,00 0,54 - 1,85 0,999
1,15 0,64 - 2,05 0,638
<=SD 1,11 0,79 - 1,54 0,552
1,01 0,62 - 1,65 0,963
0,59 0,33 - 1,06 0,079
Status kerja 2014 Bekerja 1
1
1
Tidak bekerja 1,60 1,22 - 2,09 0,001
1,15 0,78 - 1,70 0,483
1,57 1,03 - 2,38 0,035
Kebiasaan merokok 2014 Tidak pernah 1
0,006
1
0,000
1
0,001
Mantan perokok 1,76 1,00 - 3,10 0,051
0,87 0,42 - 1,78 0,696
2,49 1,14 - 5,43 0,022
Saat ini merokok 2,29 1,38 - 3,80 0,001
3,33 1,85 - 6,01 0,000
3,80 1,93 - 7,46 0,000
Aktivitas fisik 2014 Aktivitas berat 1
0,062
1
0,321
1
0,875
Aktivitas sedang 0,61 0,40 - 0,93 0,020
0,95 0,58 - 1,56 0,839
0,95 0,55 - 1,63 0,838
Tidak beraktivitas 0,87 0,67 - 1,13 0,295
0,75 0,51 - 1,10 0,138
0,90 0,59 - 1,36 0,606
Kategori IMT
1
0,019
1
0,450
1
0,019
0,82 0,61 - 1,10 0,193
0,77 0,50 - 1,18 0,227
2,08 1,20 - 3,59 0,009
1,31 0,92
1,87 0,138
0,92 0,52
1,63 0,781
1,32 0,63
2,74 0,462
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 218
Status kawin 2007 Kawin/tinggal bersama 1
0,767
1
0,902
1
0,723
Belum kawin 0,82 0,48 - 1,40 0,469
1,18 0,58 - 2,42 0,650
0,73 0,35 - 1,56 0,420
Cerai 0,77 0,09 - 6,42 0,809
0,00 0,00 - . 0,999
0,00 0,00 - . 0,999
Status kerja 2007 Bekerja 1
1
1
Tidak bekerja 0,89 0,66 - 1,19 0,425
1,64 1,09 - 2,46 0,017
1,61 0,97 - 2,66 0,063
Aktivitas fisik 2007 Aktivitas berat 1
0,362
1
0,704
1
0,566
Aktivitas sedang 0,82 0,55 - 1,22 0,333
1,01 0,58 - 1,77 0,962
0,82 0,45 - 1,50 0,522
Tidak beraktivitas 1,03 0,75 - 1,43 0,839
1,17 0,73 - 1,89 0,514
1,05 0,62 - 1,79 0,849
Kebiasaan merokok 2007 Tidak pernah 1
0,897
1
0,460
1
0,600
Mantan perokok 0,95 0,57 - 1,60 0,848
0,83 0,44 - 1,56 0,558
0,70 0,35 - 1,40 0,312
Saat ini merokok 0,85 0,43
1,69 0,642
0,55 0,22
1,42 0,219
0,82 0,33
2,04 0,665
*Depresi adalah gejala depresi yang dialami pada tahun 2007 sebelum terjadinya PTM dengan dikontrol variabel demografi dan perilaku
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 219
PEMBAHASAN
Penyakit tidak menular merupakan penghalang pembangunan. PTM dapat menggiring orang
menuju ke kemiskinan, terutama di negara dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.18
Dimana
80% penderita diabetes berada di negara berkembang.19
Diabetes merupakan gangguan metabolik
yang sudah meluas di seluruh dunia. Proporsi diabetes yang dihasilkan dalam analisis ini (4,4%)
hampir sama dengan angka diabetes pada penduduk dunia (3-4%)19
, namun sedikit lebih rendah
dari penduduk perdesaan Asia Selatan (5-6%), Vietnam (5,7%), India (6,2%) dan Srilanka (10,9%).
Penyakit paru kronik sering sulit dibedakan dengan asma. Analisis data menghasilkan proporsi
penyakit paru kronik (2%) yang lebih rendah dengan kondisi di India (4%) dan Vietnam
(6,7%).18,20
Kejadian asma dari studi ini sebesar 3,0%. Angka hampir sama dengan hasil pada
penduduk dewasa Korea(2,8%). 21
Untuk kondisi gejala depresi pada saat baseline adalah 5,3%,
angka ini sedikit lebih tinggi dari prevalensi pada penduduk dewasa Korea (4,1%).21
Individu dengan gangguan mental memiliki risiko lebih tinggi mengalami masalah penyakit
kronis. Dalam studi ini ditunjukkan bahwa diabetes pada orang dengan gejala depresi adalah
sebesar 7,2%,lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak mengalami depresi (4,3%). Diketahui
risiko seseorang dengan gejala depresi untuk mengalami diabetes adalah 1,8 kali lebih tinggi
dibandingkan orang tanpa gejala depresi. Hal ini sesuai dengan hasil meta-analisis yang
menujukkan risiko orang dengan depresi sebesar 1,60 (1,37–1,88) kali lebih tinggi mengalami
diabetes dibanding orang yang tidak menderita gejala depresi.22
Hal ini juga sejalan dengan hasil
yang menunjukkan risiko orang dengan depresi sebesar 1,2-2,6 kali lebih tinggi mengalami
diabetes dibanding orang yang tidak menderita gejala depresi.19
Ada beberapa mekanisme potensial yang berperan dalam peran depresi pada kejadian
diabetes. Individu dengan depresi lebih mungkin memiliki perubahan berat badan dan cenderung
tidak terlibat dalam perilaku sehat seperti olahraga, yang meningkatkan risiko terkena diabetes.
Selain itu, banyak obat yang digunakan untuk mengobati depresi menyebabkan penambahan berat
badan dan sedasi, seperti antidepresan trisiklik dan penghambat reuptake serotonin selektif, yang
juga dapat berkontribusi untuk memicu diabetes.23
Studi ini menunjukkan risiko orang denga gejala depresi memiliki risiko mengalami asma
sebesar 1,83 kali dibanding orang tanpa gejala depresi. Hasil ini sejalan dengan meta-analisis studi
prospektif yang menyatakan bahwa orang dengan gejala depresi memiliki risiko 1,43 kali lebih
tinggi dibandingkan individu yang tidak mengalami gejala depresi.24
Secara umum, stress dapat mempengaruhi system saraf otonom dan atau system
neuroendokrin yang akan meningkatkan risiko berkembangnya asma.25
Depresi dapat
menyebabkan asma melalui berbagai mekanisme. Pertama, depresi telah dikaitkan secara positif
dengan tingkat mediator inflamasi sistemik yang tinggi, yang memiliki peran patogen yang
mendasari asma. Kedua, depresi diketahui memiliki efek neuroendokrin (yaitu deregulasi sumbu
hipotalamus-hipofisis-adrenokortikal dan sistem saraf otonom), yang dapat memberikan hubungan
antara depresi dan asma. Ketiga, individu yang depresi cenderung menjadi gemuk dan perokok, dan
kondisi ini telah terbukti secara independen meningkatkan risiko asma. Keempat, depresi telah
dikaitkan dengan peningkatan tingkat stres oksidatif dan penurunan fungsi antioksidan, dan stres
oksidatif berkontribusi pada patogenesis asma. Secara keseluruhan, beberapa mekanisme pada
pasien dengan kerentanan genetik, baik sendiri atau gabungan, dapat berimplikasi pada munculnya
kejadian asma.24
Bahkan ibu yang mengalami stress pada masa kehamilan atau setelah
melahirkan,dapat meningkatkan risiko asma pada bayinya. Seperti hasil studi di Newyork yang
menunjukkan stress saat kehamilan dapat mengganggu system perkembangan pada bayi sehingga
bayi akan rentan terhadap asma dan perkembangan paru-paru terganggu.26
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 220
Penelitian ini menunjukkan kejadian penyakit paru kronik lebih tinggi pada responden yang
mengalami gangguan depresi (3,2%) dibandingkan pada orang tanpa gejala depresi (1,5%). Pola
yang sama juga terjadi pada populasi Amerika. Besar risiko untuk terjadinya penyakit paru kronik
pada orang dengan gejala depresi yang dihasilkan dalam analisis ini adalah 2,2 kali dibandingkan
pada orang tanpa gejala depresi. Risiko ini lebih besar dibandingkan risiko pada populasi Amerika
(OR=1,64) dan hasil meta-analisis 16 studi terkait depresi terhadap penyakit paru kronik
(OR=1,4).27,28
Gambaran fungsi paru pada orang dengan gejala depresi lebih rendah dibandingkan pada
orang tanpa gejala depresi, terutama pada kelompok umur di atas 50 tahun. Beberapa kemungkinan
mekanisme yang dapat dipertimbangkan diantaranya penurunan fungsi paru-paru mungkin terkait
dengan gejala seperti dispnea, yang dapat menyebabkan perasaan putus asa, berkurangnya aktivitas
fisik, isolasi sosial, dan gaya hidup yang tidak banyak bergerak. Semua faktor ini dapat dikaitkan
dengan peningkatan gejala depresi. Selain itu, penelitian sebelumnya menemukan bahwa hubungan
antara depresi dan fungsi paru tampaknya sebagian dimediasi oleh sitokin proinflamasi.29
KESIMPULAN DAN SARAN
Gejala depresi berhubungan dengan peningkatan peluang kejadian diabetes, asma, penyakit
paru-paru kronik dengan mempertimbangkan beberapa faktor demografi dan perilaku. Penanganan
gangguan mental sebaiknya dilakukan sebelum kondisi yang parah, dengan melibatkan perhatian
pada kesehatan fisik dan perilaku kesehatan.
DAFTAR PUSTAKA
1. Hernández-vásquez, A. Association of Comorbidities With Pneumonia and Death Among
COVID-19 Patients in Mexico : A Nationwide Cross-sectional Study Study Design and
Data Source. Journal of Preventive Medicine & Public Health, 2020, Vol.53: 211-219.
2. WHO. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Dipetik October 2020, dari
https://covid19.who.int/table. 2020.
3. Huang, C. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan ,
China. The Lancet, 2020, Vol. 395: 497-506.
4. Thapa, K. Prevalence of comorbidities among individuals with COVID-19 : A rapid review
of current literature. American Journal of Infection Control, 2020: 1-9.
5. Galdamez, D. Increased Risk of Hospitalization and Death in Patients with COVID-19 and
Pre-existing Noncommunicable Diseases and Modifiable Risk Factors in Mexico. Archives
of Medical Research, 2020.
6. Parveen, R. Association of diabetes and hypertension with disease severity in covid-19
patients: A systematic literature review and exploratory meta-analysis. Diabetes Research
and Clinical Practice, 2020.
7. WHO. Global Status Report on noncommunicable diseases. 2014.
8. MOH, N.-I. Riset Kesehatan Dasar. Jakarta. 2008.
9. Indonesian Ministry of Health, N. Penyajian Pokok-Pokok Hasil Riset Kesehatan Dasar
2013. Jakarta. 2013.
10. NIHRD, I. M. Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar 2018. Jakarta. 2018.
11. Caldas-de-almeida, J. M. Association of Mental Disorders With Subsequent Chronic
Physical Conditions World Mental Health Surveys From 17 Countries. JAMA Psychiatry,
2016., Vol. 73(2): 150-158.
12. Lawrence, D. The Epidemiology of Excess Mortality in People With Mental Illness. La
Revue canadienne de psychiatrie, 2010, Vol. 55 (12): 752-760.
13. Cunningham, R. Premature mortality in adults using New Zealand psychiatric services.
The New Zeland Medical Journal, 2014, Vol. 127: 31-41.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 221
14. Ganju, V. Non-communicable diseases and the mental health gap : what is to be done ?
papers Mental health and the World Health Organization : translating strategy into practice.
InternatIonal PsychIatry, 2012, Vol. 9(4): 79-80.
15. WHO. Depression and Other Common Mental Disorders Global Health Estimates. 2017.
16. Strauss, J. The Fifth Wave of the Indonesia Family Life Survey: Overview and Field
Report. 2016.
17. Miller, W. C. Measurement properties of the CESD scale among individuals with spinal
cord injury Measurement properties of the CESD scale among individuals with spinal cord
injury. Spinal Cord, 2008, vol. 46: 287-292.
18. Mohammed, S. Non ‐ Communicable Diseases ( NCDs ) in developing countries : a
symposium report . Globalization and Health, 2014, Vol. 10(81): 1-7.
19. Hert, M. D. Physical illness in patients with severe mental disorders . I . Prevalence ,
impact of medications and disparities in health care. World Psychiatry, 2011, Vo. 10.
20. Siegel,K. Non-communicable diseases in South Asia: contemporary perspectives,. British
Medical Bulletin, 2014, Vol.111: 31-44.
21. Choi,S. Association between depression and asthma in Korean adults.
allergyandasthmaproceedings, 2017, vol. 38 (3): 238-239.
22. Merzuk,B. Depression and Type 2 Diabetes Over the Lifespan. Diabetes Care, 2008,
Vo.31(12): 2383 – 2390.
23. Brown,L. History of Depression Increases Risk of Type 2 Diabetes in Younger Adults.
Diabetes Care, 2005, Vo. 28 (5): 1063 – 1067.
24. Ghao,Y. The Relationship between Depression and Asthma : A Meta-Analysis of
Prospective Studies. PLoS One, 2015, Vol. 10(7): 1-12.
25. Alonso, J. Association between mental disorders and subsequent adult onset asthma. J
Psychiatr Res, 2016: 179-188.
26. Rosa, M. Evidence establishing a link between prenatal and early life stress and asthma
development. Curr Opin Allergy Clin Immunol, 2018.
27. Goodwin, R. Depression , Anxiety , and COPD : The Unexamined Role of Nicotine
Dependence. Nicotine & Tobacco Research, 2012, vol. 14 (2): 176-183.
28. Atlantis,E. Bidirectional Associations Between Clinically Relevant Depression or Anxiety
and COPD. CHEST, 2013, Vol. 144 (3): 766-777.
29. Park, Y. Relationship between depression and lung function in the general population in
Korea : a retrospective cross-sectional study. International Journal of COPD, 2018, Vol.
13: 2207-2213.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 222
PERILAKU MASYARAKAT TENTANG PENCEGAHAN DEMAM BERDARAH
DENGUE DI DAERAH ENDEMIS DAN NON ENDEMIS KOTA PEKANBARU
Tyagita Widya Sari
1*, Martha Saptariza Yuliea
2, Novita Meqimiana Siregar
3, Raudhatul
Muttaqin4
1,2 Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan
Ilmu Kesehatan, Universitas Abdurrab, 3,4
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas
Abdurrab,
Jl. Riau Ujung No.73 Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia, 28292
Corresponding email : [email protected]
COMMUNITY BEHAVIOR ABOUT DENGUE HEMORRHAGIC FEVER PREVENTION
IN ENDEMIC AND NON-ENDEMIC AREAS PEKANBARU CITY
ABSTRACT
Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is an infectious disease caused by the dengue virus and transmitted
through the Aedes aegypti mosquito’s bite. DHF causes Extraordinary Events in several regions in
Indonesia, including Pekanbaru City. One of the dengue endemic areas in Pekanbaru City is the Payung
Sekaki Health Center working area, where 52 cases of DHF were reported throughout 2018 and without
deaths. The number of dengue cases increased in the January-August 2019 period by 53 cases and resulted
in 1 death (CFR = 1.89%). The work area of the Karya Wanita Rumbai Puskesmas is one of the non-endemic
areas of dengue fever in Pekanbaru City, where only 10 cases of dengue were reported in the January-
August 2019 period. The purpose of this research was to determine the comparison of community behavior
regarding DHF prevention between endemic and non-endemic areas Pekanbaru City. The study design was
an observational study with a cross sectional approach. The sampling technique used accidental sampling
method, namely 100 respondents for each working area of the puskesmas. The data analysis used the Mann
Whitney test which produced the p-value. There are differences in community behavior regarding the
prevention of DHF in endemic and non-endemic areas of Pekanbaru City with p-value 0.002 (p-value
<0.05). There are differences in community behavior regarding the prevention of DHF in endemic
and non-endemic areas. Health workers should be able to encourage the public to improve
effective and efficient DHF prevention behavior, namely the 3M Plus Mosquito Nest Eradication
(PSN) movement, including through efforts to increase knowledge and attitudes about dengue
prevention.
Keywords: DHF, Endemic, Prevention, Behavior
ABSTRAK
Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue dan
ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Terdapat Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD di beberapa
daerah di seluruh Indonesia, termasuk Kota Pekanbaru. Salah satu daerah endemis DBD di Kota Pekanbaru
adalah wilayah kerja Puskesmas Payung Sekaki, di mana dilaporkan sepanjang tahun 2018 terdapat 52 kasus
DBD dan tanpa kematian. Pada periode Januari-Agustus tahun 2019 kasus DBD ini dilaporkan meningkat
sebesar 53 kasus dan menimbulkan 1 kematian (CFR=1,89%). Wilayah kerja Puskesmas Rawat Inap Karya
Wanita Rumbai merupakan salah satu daerah non endemis DBD di Kota Pekanbaru, di mana dilaporkan
hanya terdapat 10 kasus DBD pada periode Januari-Agustus tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah
mengetahui perbandingan perilaku masyarakat tentang pencegahan DBD antara daerah endemis dan non
endemis Kota Pekanbaru. Desain studi penelitian ini merupakan studi observasional dengan pendekatan
cross sectional. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan accidental sampling, yakni
100 responden untuk masing-masing wilayah kerja puskesmas. Analisis data menggunakan uji Mann
Whitney yang menghasilkan p-value. Diperoleh p-value 0,002 (p-value < 0,05) yaitu terdapat perbedaan
perilaku masyarakat tentang pencegahan DBD di daerah endemis dan non endemis Kota Pekanbaru.
Berdasarkan hasil terdapat perbedaan perilaku masyarakat tentang pencegahan DBD di daerah endemis dan
non endemis. Tenaga kesehatan hendaknya dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan perilaku
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 223
pencegahan DBD yang efektif dan efisien yaitu melalui gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M
Plus, antara lain melalui upaya peningkatan pengetahuan dan sikap tentang pencegahan DBD.
Kata kunci : DBD, Endemis, Pencegahan, Perilaku
PENDAHULUAN
Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh
virus Dengue, di mana virus ini ditularkan oleh nyamuk Aedes Spp. Demam Berdarah Dengue
(DBD) memiliki gejala serupa dengan Demam Dengue (DD), namun DBD memiliki gejala khas
lain berupa sakit/nyeri pada ulu hati terus-menerus, perdarahan pada hidung, mulut, gusi atau
memar pada kulit. Menurut data World Health Organization (WHO) tahun 2010, Indonesia
dilaporkan sebagai negara kedua dengan kasus DBD terbesar di antara 30 negara wilayah endemis
DBD. (1)
Kasus DBD yang dilaporkan di Provinsi Riau pada tahun 2017 sebanyak 1928 kasus dan
menimbulkan 15 kematian (Case Fatality Rate/CFR=7,78%). Selanjutnya, kasus DBD di Provinsi
Riau mengalami penurunan pada tahun 2018 sebanyak 918 kasus dan menimbulkan 8 kematian
(CFR=8,71%). (1,2) Dinas Kesehatan Provinsi Riau melaporkan kasus DBD sebanyak 358 kasus
dan 2 orang meninggal (CFR=0,56%) di Kota Pekanbaru pada tahun 2018. Adapun jumlah kasus
DBD yang dilaporkan pada semester pertama tahun 2019 adalah sebanyak 274 kasus, dimana yang
terbanyak terdapat di wilayah kerja Puskesmas Payung Sekaki sebanyak 52 kasus. (3,4) Jumlah
kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Payung Sekaki meningkat, yaitu sebanyak 52 kasus dan
tanpa kematian pada tahun 2018, menjadi 53 kasus dengan 1 kematian (CFR=1,89%) pada periode
Januari-Agustus tahun 2019. Kasus DBD yang dilaporkan di wilayah kerja Puskesmas Rawat Inap
Karya Wanita Rumbai pada periode Januari-Agustus 2019 adalah 10 kasus dan tanpa kematian.
(4,5)
Jumlah penyakit tertentu yang biasanya ada dalam suatu komunitas disebut sebagai garis
dasar atau tingkat endemis penyakit. (6) Wilayah kerja Puskesmas Payung Sekaki merupakan
daerah endemis DBD, di mana kejadian DBD selalu ada dan meningkat setiap tahun. Akan tetapi,
jumlah kasus DBD yang dilaporkan di wilayah kerja Puskesmas Rumbai tidak selalu ada dan tidak
selalu meningkat setiap tahun, sehingga dikategorikan sebagai daerah non endemis DBD.
Perilaku pencegahan DBD berkaitan dengan pengetahuan dan sikap masyarakat tentang
DBD, terutama ibu, yang memiliki peranan penting dalam pemeliharaan kesehatan keluarga dan
kebersihan lingkungan rumah. Seseorang akan melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
apabila dia mengetahui dengan baik terkait tujuan dan manfaat perilaku PSN bagi kesehatan diri
dan keluarganya dalam upaya pencegahan penyakit DBD. Seseorang itu juga harus mengetahui
pula tentang bahaya atau risiko apabila tidak melakukan perilaku PSN.(6) Penelitian ini bertujuan
untuk membandingkan perilaku pencegahan DBD pada masyarakat di daerah endemis dan non
endemis Kota Pekanbaru.
METODE
Penelitian ini menggunakan desain studi observasional analitik dengan metode potong
lintang (cross sectional). Penelitian ini mempelajari hubungan antara variabel independen dengan
variabel dependen, dengan melakukan pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (7). Penelitian
ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Payung Sekaki yang dikategorikan sebagai daerah
endemis DBD dan Puskesmas Rawat Inap Karya Wanita Kota Pekanbaru yang dikategorikan
sebagai daerah non-endemis DBD. Penelitian ini dilakukan pada rentang periode bulan Juli-
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 224
Agustus 2019. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang
dikumpulkan adalah untuk mengukur perilaku pencegahan DBD ibu yang terdiri dari praktik PSN
3M Plus. Data sekunder yang dikumpulkan adalah terkait perhitungan besar sampel minimal yaitu
data jumlah penduduk perempuan yang merupakan ibu yang berdomisili di wilayah kerja
Puskesmas Payung Sekaki dan Puskesmas Rawat Inap Karya Wanita Rumbai Kota Pekanbaru pada
tahun 2018.
Sampel penelitian ini adalah sebagian penduduk perempuan yang merupakan ibu yang
berdomisili di wilayah kerja Puskesmas Payung Sekaki dan Puskesmas Rawat Inap Karya Wanita
Rumbai Kota Pekanbaru tahun 2018, yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi penelitian.
Pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel
berdasarkan kebetulan, yaitu sampel merupakan siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan
peneliti, bila dipandang orang tersebut sesuai sebagai sumber data.(7) Pengisian kuesioner
dilakukan langsung oleh peneliti berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden. Setelah
pengisian kuesioner, responden diberikan leaflet yang berisi ringkasan mengenai pengetahuan,
sikap, dan perilaku pencegahan DBD disertai penjelasan singkat oleh peneliti. Penelitian
dilaksanakan selama 7 hari, yang terdiri dari persiapan penelitian berupa Focus Group Discussion
(FGD) antara tim peneliti dan enumerator selama 1 hari, dilanjutkan dengan pengambilan data
penelitian selama 6 hari. Peneliti dibantu oleh 12 orang enumerator dalam pengambilan data
penelitian kepada responden, dimana enumerator yang merupakan mahasiswa Program Studi
Pendidikan Dokter semester 7 telah diberi pelatihan dan simulasi mengenai penelitian terlebih
dahulu.
Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan analisis univariat dilanjutkan dengan
analisis bivariat. Sebelum dilakukan uji statistik, dilakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk
mengetahui sebaran data penelitian. Uji normalitas data yang digunakan adalah uji Kolmogorov
Smirnov karena sampel yang digunakan besar (lebih dari 50 responden). Uji hipotesis yang
digunakan adalah uji korelasi Mann Whitney, karena didapatkan hasil bahwa data penelitian tidak
terdistribusi normal. Hasil uji statistik berupa nilai kemaknaan p-value.(8)
HASIL PENELITIAN
Analisis Univariat
Analisis univariat adalah analisis yang hanya menghasilkan distribusi dan persentase dari
setiap variabel, dimana analisis univariat ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan
setiap variabel penelitian. (8)
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden
No Karakteristik Responden Endemis Non Endemis
N % N %
1. Umur (tahun)
20-29 13 13,0 15 15,0 30-39 40 40,0 36 36,0
40-49 29 29,0 30 30,0
50-59 13 13,0 13 13,0
60-69 3 3,0 5 5,0 70-79 2 2,0 1 1,0
2. Pendidikan
Tidak sekolah 3 3,0 1 1,0 SD 9 9,0 11 11,0
SMP 11 11,0 12 12,0
SMA 57 57,0 55 55,0
Akademi/PT 20 20,0 21 21,0
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 225
3. Pekerjaan Buruh 0 0,0 1 1,0
PNS/TNI/Polri 1 1,0 0 0,0
Pegawai Swasta 5 5,0 7 7,0
Wiraswasta 5 5,0 8 8,0 Pekerjaan Lainnya 5 5,0 5 5,0
Ibu 84 84,0 79 79,0
4 Perilaku Tentang Pencegahan
DBD
Kurang 27 27,0 25,0 25,0
Cukup 29 29,0 18 18,0
Baik 44 44,0 57 57,0
TOTAL 100 100,0 100 100,0
Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa responden pada daerah endemis dan non endemis
paling banyak berada pada rentang umur 30-39 tahun yaitu berturut-turut sebanyak 40 orang (40%)
dan 36 orang (36%). Selain itu, sebagian besar responden pada daerah endemis dan non endemis
sama-sama memiliki tingkat pendidikan SMA yaitu berturut-turut sebanyak 57 orang (57%) dan 55
orang (55%). Selain itu, sebagian besar responden di daerah endemis sama-sama memiliki
pekerjaan sebagai ibu yaitu berturut-turut sebanyak 84 orang (84%) dan 79 orang (79%). Perilaku
pencegahan DBD responden pada daerah endemis dan non endemis paling banyak berada pada
kategori perilaku baik yaitu berturut-turut sebanyak 44 orang (44%) dan 57 orang (57%).
Analisis Bivariat
Analisis bivariat adalah analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga
berhubungan atau berkorelasi, dalam hal ini perilaku masyarakat tentang pencegahan DBD di
daerah endemis dan non-endemis. Uji statistik yang dipakai adalah uji Mann-Whitney, karena skala
data yang digunakan adalah rasio dan data penelitian terdistribusi tidak normal.(8)
Tabel 2.
Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Masyarakat Tentang Pencegahan DBD
Variabel Mann Whitney
Perilaku Masyarakat tentang Pencegahan DBD
N 200
p-value 0,002
Berdasarkan hasil uji Mann Whitney pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa perilaku masyarakat
tentang pencegahan DBD memiliki p-value < 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat
perbedaan perilaku masyarakat tentang pencegahan DBD pada daerah endemis dan non endemis
Kota Pekanbaru.
PEMBAHASAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 200 responden yang terdiri dari 100
orang ibu di wilayah kerja Puskesmas Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan 100 orang ibu di
wilayah kerja Puskesmas Karya Wanita Rumbai pada bulan Juli-Agustus 2019, diperoleh nilai
signifikansi yang bermakna antara perilaku pencegahan DBD ibu pada daerah endemis dan non
endemis yaitu p-value 0,002 (p-value < 0,05). Jadi, dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan
perilaku masyarakat tentang pencegahan DBD pada daerah endemis dan non endemis Kota
Pekanbaru.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 226
Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dimana tahu ini terjadi setelah orang melakukan
penginderaan terhadap suatu stimulus (objek) tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera
manusia antara lain indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera perasa,
dan indera peraba. Adapun, sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata yang
merupakan indera penglihatan dan telinga yang merupakan indera pendengaran. Pengetahuan
atau ranah kognitif merupakan variabel yang sangat penting dalam membentuk perilaku
seseorang. Sedangkan, sikap merupakan reaksi atau respons yang masih tertutup dari seseorang
terhadap suatu stimulus (objek) tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas,
akan tetapi sikap merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap merupakan kesiapan
untuk bereaksi terhadap stimulus (objek) di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan
terhadap stimulus (objek) tersebut.(6)
Terbentuknya perilaku baru (adopsi perilaku) pada seseorang dimulai dari seseorang harus
mengetahui dengan baik terkait pengertian dan manfaat perilaku tersebut bagi dirinya atau
keluarganya terlebih dahulu. Dalam proses adopsi perilaku baru, di dalam diri seseorang terjadi
proses yang berturutan antara lain sebagai berikut :
1. Awareness (kesadaran) yaitu seseorang menyadari atau mengetahui stimulus (objek) terlebih
dahulu,
2. Interest (ketertarikan) yaitu seseorang mulai tertarik kepada stimulus (objek) tersebut,
3. Evaluation (evaluasi) yaitu seseorang mempertimbangkan baik atau buruknya stimulus tersebut
bagi dirinya,
4. Trial (mencoba) yaitu seseorang sudah mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa
yang dikehendaki oleh stimulus (objek),
5. Adoption (adopsi) yaitu seseorang telah memiliki perilaku yang baru sesuai dengan
pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus (objek).
Dalam penelitian ini, kami menemukan bahwa ibu yang tinggal di daerah endemis
memiliki pengetahuan dan sikap yang lebih baik tentang pencegahan DBD, tetapi mereka
memiliki praktik pencegahan DBD yang lebih buruk, dibandingkan dengan ibu yang tinggal di
daerah non endemis. Hal ini mirip dengan penelitian sebelumnya di Vietnam bahwa orang yang
melaporkan kepadatan tinggi nyamuk ditemukan lebih cenderung memiliki pengetahuan yang
baik, sikap yang baik. Namun, hasilnya tidak mirip dengan penelitian sebelumnya bahwa orang
yang melaporkan kepadatan tinggi nyamuk ditemukan lebih mungkin untuk memiliki praktik
yang baik dalam pencegahan DBD. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa orang yang tinggal
di daerah berisiko tinggi atau endemis memiliki persepsi yang lebih serius terhadap penyakit
yang ditularkan oleh nyamuk seperti DBD dan DF, meskipun persepsi tidak selalu sejalan
dengan praktik.(9) Hasil penelitian ini adalah juga tidak mirip dengan penelitian lain yang
dilakukan di Selangor, Malaysia bahwa masyarakat yang tinggal di daerah non endemik wabah
demam berdarah memiliki pengetahuan dan sikap yang lebih baik tentang demam berdarah
daripada masyarakat yang tinggal di daerah endemis, tetapi tidak ada perbedaan signifikan yang
ditemukan dalam kategori praktik.(10)
Perilaku pencegahan DBD yang efektif dan efisien antara lain praktik PSN 3M Plus
berhubungan dengan kejadian DBD di suatu daerah. PSN 3M Plus adalah salah satu contoh
perilaku hidup bersih dan sehat karena berkaitan dengan upaya pencegahan penyakit DBD
dengan cara memutus daur hidup nyamuk Aedes Spp yang merupakan rantai penularan DBD.
PSN 3M Plus hendaknya dilaksanakan secara aktif, mandiri, dan terus-menerus, serta
berkesinambungan oleh seluruh lapisan masyarakat.(11) Hasil penelitian oleh Jata et al tahun
2016 menemukan bahwa ada hubungan perilaku masyarakat dalam PSN dengan kejadian DBD
di wilayah Puskesmas I Denpasar Selatan dan Puskesmas I Denpasar Timur.(12) Menurut hasil
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 227
penelitian lainnya oleh Priesley et al, terdapat hubungan yang bermakna antara perilaku PSN 3M
Plus dengan kejadian DBD di Kelurahan Andalas Kota Padang tahun 2017 (p-value =
0,001).(13)
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat perbedaan perilaku masyarakat tentang
pencegahan DBD di daerah endemis dan non endemis Kota Pekanbaru.
Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah tenaga kesehatan
hendaknya dapat senantiasa melakukan upaya peningkatan pengetahuan masyarakat di wilayah
kerjanya tentang pencegahan DBD yang efektif dan efisien yaitu melakukan Pemberantasan
Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus secara aktif, mandiri, dan berkesinambungan. Pengetahuan
responden tentang pencegahan DBD yang baik akan dapat membentuk sikap responden yang
baik terhadap pencegahan DBD sehingga dapat terwujud pada perilaku pencegahan DBD yang
baik pula. Hal ini dapat membantu dalam mengendalikan penularan dan menurunkan angka
kejadian DBD baik di daerah endemis maupun non-endemis.
DAFTAR PUSTAKA
1. Indonesian Ministry of Health. Situation of Dengue Hemorrhagic Fever in Indonesia in
2017 [Internet]. Jakarta: Center of Data and Information Indonesian Ministry of Health;
2018. Available from:
http://www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/InfoDatin-
Situasi-Demam-Berdarah-Dengue.pdf
2. Indonesian Ministry of Health. Indonesian Health Profile 2018 [Internet]. Jakarta:
Indonesian Ministry of Health; 2019. 1 p. Available from:
http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/profil-
kesehatan-indonesia-2018.pdf
3. Pekanbaru City Health Department. Data Report of Dengue Hemorrhagic Fever in
Pekanbaru City 2018. Pekanbaru; 2019.
4. Pekanbaru City Health Department. Data Report of Dengue Hemorrhagic Fever in
Pekanbaru City January-August 2019. Pekanbaru; 2019.
5. Payung Sekaki Health Center. Payung Sekaki Health Center Profile 2019. Pekanbaru; 2019.
6. Notoatmodjo S. Health Promotion and Health Behavior. Jakarta: Rineka Cipta; 2012.
7. Notoatmodjo S. Public Health : Science and Art. Jakarta: Rineka Cipta; 2011.
8. Notoatmodjo S. Health Research Methodology. Jakarta: Rineka Cipta; 2015.
9. Nguyen H Van, Than PQT, Nguyen TH, Vu GT, Hoang CL, Tran TT, et al. Knowledge,
attitude and practice about dengue fever among patients experiencing the 2017 outbreak in
vietnam. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(6).
10. Ghani NA, Shohaimi S, Hee AKW, Chee HY, Emmanuel O, Ajibola LSA. Comparison of
knowledge, attitude, and practice among communities living in hotspot and non-hotspot
areas of dengue in Selangor, Malaysia. Trop Med Infect Dis. 2019;4(1):1–10.
11. Indonesian Ministry of Health. Technical Guidance for PSN 3M Plus Implementation with
1 Home 1 Jumantik Movement. Jakarta: Indonesian Ministry of Health; 2016. 49–51 p.
12. Jata D, Adi Putra N, Pujaastawa IBG. The Correlation between Community Behavior in the
Mosquito Breeding Place Eradication and Environmental Factors with the Dengue
Hemorrhagic Fever Event in the Region of Health Center I South Denpasar and Health
Center I East Denpasar. ECOTROPHIC J Ilmu Lingkung (Journal Environ Sci [Internet].
2016;10(1):17. Available from:
https://ojs.unud.ac.id/index.php/ECOTROPHIC/article/view/21516/14216
13. Priesley F, Reza M, Rusjdi SR. The Correlation between Mosquito Breeding Place
Eradication Behavior by PSN 3M Plus to the Occurrence of Dengue Hemorrhagic Fever in
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 228
Andalas Village, Padang, West Sumatra. J Kesehat Andalas. 2018;7(1):124–30.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 229
DETERMINAN PEMILIHAN ALAT KONTRASEPSI
DI PUSKESMAS MAKRAYU PALEMBANG
Farina Eka Agustine,
1 Dian Safriantini
2 *
1Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya
2Bagian Administrasi Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya
Jl. Palembang Prabumulih KM. 32, Indralaya Indah Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan
Corresponding email : [email protected]
DETERMINANTS OF CONTRACEPTION METHOD SELECTION
IN PUSKESMAS MAKRAYU, PALEMBANG
ABSTRACT
The rapid population growth as a result of high fertilization rates is one of the causes of poverty and a
barrier to economic growth. To address this problem, the government requires couples of childbearing age
to take part in the Family Planning (KB) program, one of which is through the use of contraception. This
study aims to determine the determinant factors that influence the choice of contraceptives method at
Makrayu Health Center in Palembang. The research design was cross sectional, with a quantitative
approach. The sample in this study amounted to 80 people. The sampling technique was accidental sampling.
Data analysis was performed using univariate and bivariate methods. Bivariate analysis using the Chi-
Square test. The role of medical officers is an influencing factor in the selection of contraceptives method for
women of fertile age (WUS). The higher role of a health worker has a chance of 1,278 times greater than the
lower one. The variables of education, occupation, knowledge, availability of contraceptives and husband's
support had no relationship with the choice of contraceptives. There is a need to increase the role of health
workers who handle the contraceptive division to provide education about contraceptives to the public on a
regular basis so that people are better able to identify the suitable contraceptives method for their condition
in order to manage the births.
Keywords: Family Planning, Contraception, Women of Childbering Age (WUS)
ABSTRAK
Laju pertumbuhaan penduduk yang pesat akibat dari tingkat fertilisasi yang tinggi menjadi salah satu
penyebab kemiskinan dan penghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah
mewajibkan pasangan usia subur untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB) salah satunya melalui
penggunaan kontrasepsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan factor yang mempengaruhi
pemilihan alat kontrasepsi di Puskesmas Makrayu Palembang. Desain penelitian adalah cross sectional,
dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 80 orang. Teknik pengambilan sampel
secara accidental sampling. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariate. Analisis bivariat
menggunakan uji Chi-Square. Peran petugas menjadi faktor yang berpengaruh dalam pemilihan alat
kontrasepsi pada Wanita Usia Subur (WUS). Peran petugas kesehatan yang tinggi memiliki peluang 1,278
kali lebih besar dibandingkan dengan peran petugas kesehatan yang rendah. Variabel pendidikan, pekerjaan,
pengetahuan, ketersediaan alat kontrasepsi dan dukungan suami tidak terdapat hubungan dengan pemilihan
alat kontrasepsi. Perlunya meningkatkan peran petugas kesehatan yang menangani bagian alat kontrasepsi
untuk memberikan edukasi mengenai alat kontrasepsi kepada masyarakat secara rutin agar masyarakat lebih
mampu untuk mengidentifikasi alat kontrasepsi yang sesuai dengan keadaannya guna mengatur jumlah
kelahiran yang diharapkan.
Kata Kunci: Keluarga Berencana, Alat Kontrasepsi, Wanita Usia Subur (WUS)
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 230
PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki permasalahan dengan jumlah
penduduk yang besar namun persebarannnya tidak merata dan memiliki kualitas yang rendah.
Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan ke empat terbesar di dunia setelah Negara China,
India dan Amerika Serikat. Berdasarkan data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015,
jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 255.18 juta jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar
pertumbuhan sebesar 1,43 persen per tahun1.
Pemerintah Republik Indonesia telah mewajibkan pasangan usia subur untuk mengikuti
program Keluarga Berencana (KB) dalam hal mengatasi masalah laju pertumbuhan penduduk.
Salah satu upaya yang dilakukan di Program KB adalah penggunaan alat kontrasepsi. Kontrasepsi
berperan dalam hal mencegah kehamilan2. Data yang dikeluarkan World Health Organization
(WHO) pada tahun 2013 menginformasikan bahwa penggunaan alat kontrasepsi di Indonesia
adalah sebesar 61%. Angka ini telah melebihi angka rata-rata penggunaaan alat kontrasepsi di
Negara ASEAN (58,1%), namun lebih rendah jika dibandingka dari Negara Vietnam (78%),
Kamboja (79%) dan Thaniland (80%). Padahal jumlah Wanita Usia Subur di Indoneisa adalah
tertinggi di kawasan ASEAN dengan jumlah sebesar 65 juta jiwa3.
Jenis alat kontrasepsi terbagi menjadi dua jenis yaitu alat kontrasepsi modern dan alat
kontrasepsi tradisional. Jenis alat kontrasepsi modern memiliki risiko kegagalan yang lebih kecil
jika dibandingkan alat kontrasepsi tradisional. Namun jenis alat kontrasepsi modern memiliki biaya
yang lebih besar dikarenakan perlu dilakukan secara berulang. Jenis alat kontrasepsi tradisional
tentunya lebih murah karena tidak membutuhkan biaya, alat maupun obat- obatan2.
Propinsi Bengkulu merupakan propinsi yang memiliki cakupan peserta KB aktif tertinggi di
Indonesia yaitu sebesar 71,15%. Sedangkan Propisni Papua memiliki cakupan peserta KB aktif
terendah di Indonesia yaitu 25,73%. Jika dilihat dari target nasional Propinsi Sumatera Selatan
berada di posisi 9 (Sembilan) dalam capaian target nasional yaitu sebesar 66,80% dari 57.436 jiwa
pasangan (PUS)4
Di Kota Palembang, cakupan peserta KB aktif tertinggi berada di Kecamatan
Kalidoni (20.730 PUS) dan cakupan terendah di Kecamatan Bukit Kecil (3.805 PUS)5.
Beberapa penelitian menemukan factor-faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan jenis
alat kontrasepsi. Penelitian yang dilakukan oleh Simbolon mendapatkan hasil bahwa pengetahuan
dan peran dari petugas kesehatan memiliki hubungan terhadap pemilihan jenis alat kontrasepsi6.
Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah juga mendapatkan hasil bahwa tingkat pendidikan dan
dukungan suami memiliki hubungan terhadap pemilihan jenis alat kontrasepsi7.Penelitian Supriadi
juga menemukan bahwa pekerjaan memiliki hubungan terhadap pemilihan jenis alat kontrasepsi8.
Ketersediaan alat kontrasepsi juga memiliki hubungan dengan pemilihan jenis alat kontrasepsi9.
Sebagai satu-satunya puskesmas di wilayah Kecamatan Ilir Barat II, Puskesmas Makrayu
memiliki jumlah peserta KB aktif 10.628 jiwa atau 82.57% pada tahun 2017 dan menurun menjadi
8.957 jiwa atau sebesar 79.2% pada tahun 20185. Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini
adalah menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan wanita usia subur (WUS) dalam
memilih alat kontrasepsi.
METODE
Desain penelitian adalah cross sectional, dengan pendekatan kunatitatif. Populasi dalam
penelitian ini adalah Wanita Usia Subur (WUS) yang merupakan akseptor KB di wilayah kerja
Puskesmas Makrayu Palembang.Sampel dalam penelitian ini berjumlah 80 orang. Teknik
pengambilan sampel secara Accidental Sampling. Cara pengumpulan data nya adalah wawancara
dengan instrumen kuesioner. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah alat tulis, kuesioner,
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 231
informed consent dan PSP.Analisa data dilakukan secara univariat dan bivariate. Analisa bivariat
menggunakan uji analisis Chi-Square dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan tingkat
kemaknaan (α) sebesar 5%.
HASIL PENELITIAN
Analisis Univariat
Analisis univariat dalam penelitian ini terdiri dari distribusi pemakaian alat kontrasepsi
responden dan distribusi karakteristik responden. Hasil analisis univariat secara rinci akan
ditampilkan pada Tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karaktersitik Wanita Usia Subur (WUS)
di Wilayah Kerja Puskesmas Makrayu Palembang
Variabel Total Responden
n %
Variabel Dependen
Pemilihan Alat Kontrasepsi Modern 72 90%
Tradisional 8 10%
Variabel Independen
Pendidikan Tinggi 76 95,0
Rendah 4 5,0
Pekerjaan
Bekerja 29 36,3
Tidak Bekerja 51 63,7
Pengetahuan
Tinggi 64 80,0
Rendah 16 20,0
Ketersediaan Alat Kontrasepsi
Ya 35 43,8
Tidak 45 56,2
Dukungan Suami Mendukung 48 60,0
Tidak Mendukung 32 40,0
Peran Petugas Kesehatan
Tinggi 50 62,5 Rendah 30 37,5
Berdasarkan Tabel 1 diatas, responden yang memilih alat kontrasepsi modern sebanyak
90,0%. Mayoritas responden berpendidikan tinggi dengan persentase 95,0%. Responden yang
tidak bekerja lebih banyak dibandingkan dengan responden yang tidak bekerja dengan persentasi
63,7%. Dilihat dari tingkat pengetahuan responden yang dominan dengan pengetahuan tinggi yaitu
sebesar 80,0%. Responden yang mengatakan tidak pada ketersediaan alat kontrasepsi lebih besar
dibandingkan dengan yang mengatakan ya dengan persentase 56.2%. Suami yang mendukung pada
responden memiliki persentase lebih tinggi yaitu sebesar 60,0%. Responden dengan peran petugas
kesehatan tinggi persentasenya yaitu 62,5%.
Analisis Bivariat
Analisis bivariat dilakukan untuk meengetahui hubungan antara variabel independen yaitu
pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, ketersediaan alat kontrasepsi, dukungan suami dan peran
tenaga kesehatan dengan variabel dependen yaitu pemilihan alat kontrasepsi pada wanita usia subur
(wus) di wilayah kerja Puskesmas Makrayu Palembang yang dijelaskan dalam Tabel 2 berikut:
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 232
Tabel 2. Hubungan Pemilihan Alat Kontrasepsi Dengan Pendidikan, Pekerjaan,
Pengetahuan, Ketersediaan Alat Kontrasepsi, Dukungan Suami dan Peran Petugas
Kesehatan Di Wilayah Kerja Puskesmas Makrayu Palembang
Variabel
Pemilihan Alat Kontrasepsi
Total
p-value
PR
(95% CI)
Modern Tradisional
N % n % n %
Pendidikan
0,350
1,211 (0,648-2.141)
Tinggi 69 90,8 7 9,2 76 100,0
Rendah 3 75,0 1 25,0 4 100,0
Pekerjaan
0,131
0,879
(0,735-1,052) Bekerja 24 82,8 5 17,2 29 100,0
Tidak Bekerja 48 94,1 3 5,9 51 100,0
Pengetahuan
1,000
0,950
(0,815-1,107) Tinggi 57 89,1 7 10,9 64 100,0
Rendah 15 93,8 1 6,2 16 100,0
Ketersediaan Alat
Kontrasepsi
0,073
1,150
(1,002-1,320) Ya 34 97,1 1 2,9 35 100,0
Tidak 38 84,4 7 15,6 45 100,0
Dukungan Suami
0,054
1,179
(0,989-1,407)
Mendukung 46 95,8 2 4,2 48 100,0
Tidak Mendukung 26 81,3 6 18,7 32 100,0
Peran Petugas
Kesehatan
0,004
1,278
(1,045-1,563) Tinggi 49 98,0 1 2,0 50 100,0
Rendah 23 76,7 7 23,3 30 100,0
Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa ada hubungan antara peran petugas kesehatan (p-
value = 0,004) dengan pemilihan alat kontrasepsi sedangkan tidak ada hubungan antara pendidikan
(p-value = 0,350), pekerjaan (p-value = 0,131), pengetahuan (p-value = 1,000), ketersediaan alat
kontrasepsi (p-value = 0,073) dan dukungan suami (p-value = 0,054) dengan pemilihan alat
kontrasepsi.
PEMBAHASAN
Hubungan Pendidikan Dengan Pemilihan Alat Kontrasepsi
Pendidikan adalah jenjang latar belakang sekolah yang berhasil ditamatkan oleh seseorang
dan ditandai dengan adanya ijazah. Di Indonesia, pendidikan wajib adalah 12 tahun yaitu dari
Sekolah Dasar (SD)-Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Akhir (SMA)10
.
Pendidikan mempunyai pengaruh positif terhadap pemakaian alat kontrasepsi. Dalam hal ini
pendidikan dikaitkan dengan informasi yang didapatkan. Informasi mengani kebutuhan untuk
menunda atau membatasi jumlah anak11
.
Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa responden yang pendidikannya tinggi sebanyak 76
responden dan yang pendidikannya rendah sebanyak 4 responden. Ibu yang memilih alat
kontrasepsi modern didominasi oleh ibu yang pendidikannya tinggi dengan jumlah 69 responden
(90,8%). Hasil penelitian ini menunjukkaan bahwa responden yang lebih banyak memilih alat
kontrasepsi modern adalah responden yang pendidikannya tinggi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pendidikan dan pemilihan
alat kontrasepsi di wilayah kerja Puskesmas Makrayu Palembang (nilai p = 0,350 atau p > 0,05).
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 233
Hasil tersebut disebabkan karena baik responden yang berstatus pendidikan tinggi dan pendidikan
rendah memilih untuk menggunakan alat kontrasepsi modern. Hal ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan Grestasari yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pendidikan dan
pemilihan alat kontrasepsi dengan nilai p = 0,05512
. Hal ini berbeda dengan penelitian yang
dilakukan oleh Fatimah yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan terhadap
pemilihan jenis alat kontrasepsi dengan nilai p = 0,0007. Demikian pula penelitian yang dilakukan
oleh Lontaan yang mendapatkan hasil bahwa ada hubungan antara pendidikan dengan pemilihan
alat kontrasepsi (p = 0,000)13
.
Hubungan Pekerjaan Dengan Pemilihan Alat Kontrasepsi
Pekerjaan adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan
penghasilan. Seseorang akan menghabiskan banyak waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan
yang dianggaapnya penting sehingga berpengaruh terhadap sedikitnya waktu untuk memperoleh
tambahan informasi yang lain 14
.
Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa responden yang bekerja sebanyak 29 responden dan
yang tidak bekerja sebanyak 51 responden. Ibu yang memilih alat kontrasepsi modern didominasi
oleh ibu yang tidak bekerja dengan jumlah 48 responden (94,1%). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan dan pemilihan alat kontrasepsi di wilayah kerja
Puskesmas Makrayu Palembang ( nilai p = 0,131 atau p > 0,05). Hal tersebut disebabkan karena
mayoritas ibu yang tidak bekerja maupun yang bekerja sama-sama memilih untuk menggunakan
alat kontrasepsi modern. Beberapa responden yang bekerja mengatakan bahwa dengan
menggunakan alat kontrasepsi modern maka tidak perlu sibuk untuk mengingat kapan waktunya
masa subur karena mereka sedikit memiliki waktu luang untuk memikirkan hal selain pekerjaan
dan keluarga. Selain itu, nilai waktu yang dimiliki ibu yang bekerja lebih mahal dibandingkan
dengan ibu yang tidak bekerja15
.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriadi yang menunjukkan
hasil bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan dan pemilihan alat kontrasepsi dengan nilai p =
0,9608. Hasil penelitian lainnya juga menunjukan tidak ada hubungan yang bermakna antara
pekerjaan dengan pemilihan alat kontrasepsi dengan nilai p = 0,0616
. Namun hasil ini tidak sejalan
dengan penelitian yang dilakukan Megawati yang menunjukkan bahwa pekerjaan memiliki
hubungan terhadap pengetahuan tentang alat kontrasepsi dengan nilai p = 0,00917
.
Hubungan Pengetahuan Dengan Pemilihan Alat Kontrasepsi
Pengetahuan adalah hasil dari ―tahu‖ setelah melakukan penginderaan terhadap objek
tertentu melalui indera-indera manusia seperti indera penglihatan, indera pendengaran, indera
penciuman, indera perasa dan juga indera peraba. Pengetahuan sebagian besar dihasilkan dari
indera penglihatan dan juga indera pendengaran (mata dan telinga). Pengetahuan yang baik tentang
kontrasepsi tentu dapat memberikan peluang untuk dapat memilih kontrasepsi dengan benar dan
baik sesuai dengan kondisi diri18
. Pengetahuan memiliki 6 (enam) tingkatan, yaitu Tahu (know);
Memahami (comprehension); Aplikasi (application); Analisis (analysis) Sintesis (synthesis);
Evaluasi (evaluation) antara lain19
:
Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa responden yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi
sebanyak 64 responden dan yang memiliki tingkat pengetahuan rendah sebanyak 16 responden. Ibu
yang memilih alat kontrasepsi modern didominasi oleh ibu yang memiliki tingkat pengetahuan
yang tinggi dengan jumlah 57 responden (89,1%).
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 234
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan dan pemilihan
alat kontrasepsi di wilayah kerja Puskesmas Makrayu Palembang (nilai p = 1,000 atau p > 0,05).
Meskipun WHO (1984) mengatakan bahwa pengetahuan dapat dijadikan sebuah
pertimbangan guna membentuk prilaku tertentu, didasarkan pertimbangkan untung-rugi, manfaat
dan sumber daya maupun uang yang tersedia dan sebagainya, namun responden yang memiliki
tingkat pengetahuan tinggi dalam penelitian ini tidak semuanya memilih untuk menggunakan alat
kontrasepsi modern dan hampir seluruh ibu yang memilih alat kontrasepsi tradisional adalah ibu
yang tingkat pengetahuannya tinggi dengan jumlah 7 dari 8 responden. Hal ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Ahmad yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara
pengetahuan ibu usia muda dan ibu usia remaja terhadap pemilihan alat kontrasepsi dengan nilai p
masing-masing adalah 0,400 dan 1,00020
. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang
dilakukan Simbolon bahwa tingkat pengetahan memiliki hubungan terhadap pemilihan jenis alat
kontrasepsi dengan nilai p = 0,0036. Penelitia yang dilakukan Syukaisih juga mendapatkan hasil
bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan pemilihan alat kontrasespsi (p = 0,000)21
.
Pengetahuan dipengaruhi oleh pengalaman seseorang, faktor lingkungan dan sosial budaya
yang kemudian pengalaman tersebut diketahui, dipersepsikan dan diyakini sehingga menimbulkan
suatu motivasi serta niat untuk bertindak sehingga terjadi perwujudan niat berupa perilaku. Oleh
karena itu, banyak faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang yang membuat hasil
penelitian ini menghasilkan hubungan yang tidak signifikan, salah satunya adalah faktor
lingkungan dan faktor budaya.
Hubungan Ketersediaan Alat Kontrasepsi Dengan Pemilihan Alat kontrasepsi
Pelayanan Kontrasepsi adalah bagian dari pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang belum
terintegrasi secara keseluruhan terhadap pelayanan komponen yang lain daripada kesehatan
reproduksi. Alasan mengapa pelayanan kontrasepsi tidak termanfaatkan anatara lain adalah karena
kelengkapan alat dan jenis kontrasepsi kurang tersedia sehingga masyarakat tidak memiliki
kesempatan untuk menggunakan alat kontrasepsi tersebut. Alasan lainnya adalah karena rendahnya
akses untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan keinginan dari masyarakat tersebut22
.
Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa responden yang mengatakan bahwa ketersediaan alat
kontrasepsinya lengkap sebanyak 35 responden dan yang tidak sebanyak 45 responden. Ibu yang
memilih alat kontrasepsi modern didominasi oleh ibu yang mengatakan bahwa ketersediaan alat
kontrasepsinya tidak lengkap dengan jumlah 38 responden (84,4%). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tidak ada hubungan antara ketersediaan alat kontrasepsi dan pemilihan alat kontrasepsi di
wilayah kerja Puskesmas Makrayu Palembang (nilai p = 0,073 atau p > 0,05).
Hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukan hasil bahwa ketersediaan
alat kontrasepsi memiliki hubungan dengan pemilihan jenis alat kontrasepsi dengan nilai p =0,0399.
Perbedaan ini dapat disebabkan karena responden terkadang dan bahkan tidak pernah bertanya
mengenai jenis alat kontrasepsi apa saja yang tersedia kepada petugas kesehatan sesaat sebelum
pelaksaan penggunaan kontrasepsi.
Hubungan Dukungan Suami Dengan Pemilihan Alat Kontrasepsi
Dukungan suami adalah bentuk perhatian yang diberikan suami kepada istri dalam
memberikan bantuan baik berupa motivasi, perhatian, penerimaan serta dorongan. Metode
kontrasepsi tertentu tidak dapat digunakan tanpa adanya kerjasama suami. Kesadaran akan fertilitas
membutuhkan kerjasama dan juga rasa saling percaya antara pasangan suami istri. Keadaaan ideal
yang mebutuhkan kerja sama antara pasangan sumi istri antara lain :
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 235
a. Suami istri bersama-sama memilih jenis alat kontrasepsi terbaik
b. Suami istri bekerjasama dalam pemakaian alat kontrasepsi
c. Suami istri bersama-sama membiayai pengeluaran untuk alat kontrasepsi
d. Suami istri bersama-sama memperhatikan tanda bahaya dari alat kontrasepsi23
.
Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa responden yang memiliki dukungan suami tinggi
sebanyak 48 responden dan yang memiliki dukungan suami rendah sebanyak 32 responden. Ibu
yang memilih alat kontrasepsi modern didominasi oleh ibu yang dukungan suaminya tinggi yang
berjumlah 46 responden (95,8%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara
dukungan suami dan pemilihan alat kontrasepsi di wilayah kerja Puskesmas Makrayu Palembang(
nilai p = 0,054 atau p < 0,05). Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukan bahwa
tidak ada hubungan antara dukungan suami dengan pemilihan alat kontrasepsi dengan nilai p =
0,01438. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian lain yang menunjukan hasil bahwa dukungan suami
memiliki hubungan dengan pemilihan jenis alat kontrasepsi dengan nilai p = 0,0007. Perilaku
seseorang dalam mengambil keputusan didasari oleh adanya kebebasan pribadi untuk mengambil
keputusan, terlebih jika suami memberikan seluruh keputusan tersebut kepada istri dalam memilih
alat kontrasepsi yang dirasa cocok untuk digunakan18
.
Hubungan Peran Petugas Kesehatan Dengan Pemilihan Alat Kontrasepsi
Informasi-informasi mengenai jenis, cara ataupun efektivitas merupakan hal utama yang
harus dimiliki pos pelayanan KB sesuai dengan metode kontrasepsi yang diberikan. Jika pelayanan
yang diberikan petugas kesehatan kurang baik dan kurang berkualitas, maka harapan untuk
pemanfaatannya pun semakin kecil. Persepsi seseorang terhadap petugas kesehatan merupakan
suatu cermin kesiapan dalam bereaksi terhadap objek tertentu, yang dalam hal ini adalah memilih
alat kontrasepsi6.
Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa responden dengan peran petugas kesehatan yang tinggi
sebanyak 50 responden dan peran petugas kesehatan yang rendah sebanyak 30 responden. . Ibu
yang memilih alat kontrasepsi modern didominasi oleh ibu dengan peran peran petugas yang tinggi
dan memilih alat kontrasepsi modern sebanyak 49 responden (98,0%). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ada hubungan antara peran petugas kesehatan dan pemilihan alat kontrasepsi
di wilayah kerja Puskesmas Makrayu Palembang (nilai p = 0,004 atau p < 0,05).
Sesuai dengan Teori Stimulus-Organisme-Rasksi (SOR) oleh Skiner yang mengatakan
bahwa pengertian yang diberikan oleh pihak lain akan menghasilkan respon yang positif, dapat
berupa perubahan perilaku sesuai dengan informasi yang diberikan. Dapat disimpulkan bahwa
peran petugas kesehatan dalam memberikan informasi-informasi terkait alat kontrasepsi yang
sesuai dengan kondisi masing-masing responden berpengaruh dalam pemilihan alat kontrasepsi
yang dilakukan responden.
Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil bahwa peran petugas
kesehatan memiliki hubungan dengan pemilihan jenis alat kontrasepsi dengan nilai p = 0,0166.
Peran petugas kesehatan yang tinggi pada wanita usia subur (WUS) di Puskesmas Makrayu
Palembang memiliki peluang 1,278 kali lebih besar untuk memilih alat kontrasepsi modern
dibandingkan dengan peran petugas kesehatan yang rendah (PR= 1,278; CI= 95%; 1,045-1,563).
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa determinan factor yang mempengruhi
pemilihan alat kontrasepsi pada Wanita Usia Subur (WUS) di wilayah kerja Puskesmas Makrayu
Palembang adalah peran petugas kesehatan dengan nilai p = 0,004. Peran petugas kesehatan yang
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 236
tinggi memiliki peluang 1,278 kali lebih besar dibandingkan dengan peran petugas kesehatan yang
rendah (PR= 1,278; CI= 95%; 1,045-1,563).
Variabel pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, ketersediaan alat kontrasepsi dan dukungan
suami tidak terdapat hubungan dengan pemilihan alat kontrasepsi pada Wanita Usia Subur (WUS)
di wilayah kerja Puskesmas Makrayu Palembang.
Saran pada penelitian ini adalah:
1. Puskesmas Makrayu : Meningkatkan peran petugas kesehatan yang menangani bagian alat
kontrasepsi untuk memberikan edukasi mengenai alat kontrasepsi kepada masyarakat secara
rutin agar masyarakat lebih mampu untuk mengidentifikasi alat kontrasepsi yang sesuai dengan
keadaannya guna mengatur jumlah kelahiran yang diharapkan.
2. Peneliti selanjutnya : Mengidentipikasi factor-faktor yang lain seperti paritas, sosial, ekonomi,
sikap, status kesehatan, pengalaman dan sebagainya. Selain itu, diharapkan juga dapat
melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif sehingga pengumpulan datanya secara
wawancara mendalam.
DAFTAR PUSTAKA
1. BPS (Badan Pusat Statistik). 2016. Profil Penduduk Indonesia Hasil Supas 2015. Jakarta:
Badan Pusat Statistik
2. Proverawati, A. 2010. Panduan Memilih Kontrasepsi. Yogyakarta: Nuha Medika
3. Kemenkes. 2013. Situasi Keluarga Berencana di Indonesia. Jakarta: Kementrian Kesehatan
4. Kemenkes. 2019. Profil Kesehatan Indonesia 2018. Jakarta: Kementrian Kesehatan
5. Dinkes Kota Palembang. 2019. Profil Puskesmas Kota Palembang Tahun 2018.
Palembang: Dinas Kesehatan Kota Palembang
6. Simbolon, Marlina L. 2017. Faktor-faktor Yang mempengaruhi Akseptor KB Dalam
pemakaian Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) Di Puskesmas Tegal Sari III Medan
Sumatera Utara Tahun 2017 [TESIS]. Medan: Universitas Sumatera Utara
7. Fatimah, D. 2013. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Alat Kontrasepsi
Dalam Rahim (AKDR) Di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo Jakarta
Timur [skripsi]. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
8. Supriadi. 2017. Faktor Yang Berhubungan Dengan penggunaan Alat Kontrasepsi Pada
Pasangan Usia subur Di Wilayah Kerja Puskesmas Kapasa [skripsi]. Makassar: Universitas
Hasanuddin
9. Musu, Appriana B. 2012. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemakaian
Kontrasepsi Implan Pada Akseptor KB Di Puskesmas Ciomas Kecamatan Ciomas,
Kabupaten Bogor Tahun 2012 [skripsi]. Depok: Universitas Indonesia
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran
Negara RI Tahun 2003. Jakarta
11. Notoatmojo, Soekidjo. 2005. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta
12. Grestasari, Luluk Erdika. 2014. Hubungan Antara Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Dan
Usia Ibu PUS Dengan Pemilihan Jenis Kontrasepsi Di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo
Kabupaten Sragen [skripsi]. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
13. Lontaan, Anita., Kusmiyati., Robin Dompas. 2014. Faktor-Faktor Yang Berhubungan
Dengan Pemilihan Kontrasepsi Pasangan Usia Subur Di Puskesmas Damau Kabupaten
Talaud. Jurnal Ilmiah Bidan. Vol.2 (1): 27-32
14. Notoatmojo, Soekidjo. 2010. Metodologi Penelitian Kesehatan Edisi Revisi. Jakarta:
Rineka Cipta
15. Nuraidah. 2011. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemilihan Alat Kontrasepsi
MKET dan Non MKET Pada Akseptor KB Di Kelurahan Pasir Putih Dan Bungo Timur
Kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo Jambi Periode 1999/ 2000 [TESIS]. Jakarta:
Universitas Indonesia
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 237
16. Hartini, Lia. 2019. Hubungan Pendidikan Dan Pekerjaan Ibu Dengan Pemakaian Alat
Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR). Jurnal Kesmas Asclepius (JKA). Vol.1 (2): 126-135
17. Megawati, Tobing., kolibu Febi., Rumayar Adisty. 2015. Hubungan Antara Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Penggunaan KB Dengan Pengetahuan Tentang KB Di Wilayah Kerja
Puskesmas Kapitu Kecamatan Amurang Barat. Jurnal Ilmiah Farmasi. Vol.4 (4): 312-319
18. Asih, Leli dan Hadriah Oesman. 2009. Analisa Lanjut SDKI 2007: Faktor-faktor Yang
Mempengaruhi Pemakaian Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Jakarta: BKKBN
19. Notoatmojo, Soekidjo. 2003. Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta
20. Ahmad, S., Esther Hutagaol dan Reginus Malara. 2014. Hubungan Pengetahuan Ibu Usia
Remaja Dan Dewasa Muda Tentang KB Dengan Penggunaan Alat Kontrasepsi Setelah
Melahirkan Di Puskesmas Mabapura Kabupaten Halmahera Timur. Jurnal Keperawatan.
Vol.2(2): 1-7
21. Syukaisih. 2015. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemilihan Kontrasepsi Di
Puskesmas Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Kesehatan Komunitas. Vol.3 (1):
34-40
22. BKKBN. 2010. Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar, Rumah Sakit
Pemerintah Swasta Dan LSM Dalam Pelayanan KB Tahun 2010-2014. Jakarta: BKKBN
Hartanto, Hanafi. 2003. Keluarga Berencana dan Kontrasepsi. Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 238
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PEMULIHAN (PMT-P) PADA BALITA
GIZI KURANG DITINJAU DARI TEORI PERILAKU TERENCANA (TPB)
Ersa Yolanda¹, Fatmalina Febry² ¹Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya
²Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya
Jl. Palembang Prabumulih KM.32 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan
Corresponding email : [email protected]
PROVIDING ADDITIONAL FOOD RECOVERY IN UNDERNUTRITION CHILDREN
UNDER FIVE REVIEWED FROM THEORY OF PLANNED BEHAVIOR (TPB)
ABSTRACT
Undernutrition is a health problem in toddlers caused by a deficiency or imbalance of nutrients the body
needs. Riskesdas data shows that there is almost no decrease in the prevalence of malnourished children
under five in Indonesia from year to year. Providing additional food recovery (PMT-P) is one of the
government programs to address undernutrition in children under five. The purpose of this research is how
to provide additional recovery food (PMT-P) for undernutrition children under five reviewed from the
theory of planned behavior (TPB). This study was an observational analytic survey with a cross sectional
design. Data were analyzed and performed univariate and bivariate analysis. Samples were women who
had malnourished children under five and received 127 PMT-P biscuits. The results showed that there was
a relationship between attitudes, subjective norms and perceived behavioral control with the mother's
intention to provide additional recovery food (PMT-P). The intention of the mother in giving additional food
to toddlers can be formed from positive maternal attitudes, supportive subjective norms and perceptions of
good maternal behavior control.
Keyword : Providing additional food recovery (PMT-P), undernutrion children under five. Theory of
Planned Behavior (TPB)
ABSTRAK
Gizi kurang merupakan gangguan kesehatan yang dialami balita yang disebabkan kekurangan atau tidak
seimbangnya zat gizi yang diperlukan tubuh. Data Riskesdas menunjukan bahwa hampir tidak ada
penurunan prevalensi balita gizi kurang di Indonesia dari tahun ke tahun. Pemberian Makanan Tambahan
Pemulihan (PMT-P) merupakan salah satu program pemerintah untuk mengatasi masalah gizi kurang pada
balita. Tujuan penelitian ini bagaimana Pemberian PMT-P pada balita gizi kurang dilihat dari Teori Perilaku
Terencana (TPB). Penelitian ini adalah survey analitik observasional menggunakan desain cross sectional.
Data penelitian diolah dan dilakukan analisis univariat dan bivariat. Sampel adalah ibu yang mempunyai
balita gizi kurang dan menerima biskuit PMTP sebanyak 127 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
ada hubungan antara sikap, norma subjektif dan persepsi control perilaku dengan niat ibu dalam pemberian
makanan tambahan pemulihan (PMT-P). Niat ibu dalam pemberian makanan tambahan pada balita dapat
terbentuk dari sikap ibu yang positif, norma subjektif yang mendukung dan persepsi kontrol perilaku ibu
yang baik.
Kata Kunci : Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P), balita gizi kurang, Teori Perilaku
Terencana
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 239
PENDAHULUAN
Balita memiliki resiko tinggi terjadi masalah gizi, karena pada usia ini proses
perkembangan anak sangat pesat sehingga membutuhkan asupan gizi untuk memenuhi
kebutuhannya1,2
. Kekurangan zat gizi yang tidak mencukupi baik kuantitas maupun kualitas dapat
menyebabkan anak kurang gizi dan mempunyai dampak yang sangat luas yaitu menyebabkan
kesakitan dan kematian, terganggunya aspek psikososial dan perkembangan intelektual sehingga
dapat mempengaruhi kecerdasan anak dan berdampak pada pembentukan kualitas sumber daya
manusia di masa mendatang3,4
.
Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Indonesia masih memiliki masalah
gizi kurang pada balita. Prevalensi balita gizi kurang pada tahun 2007 yaitu 13,0%, pada tahun
2010 prevalensi balita gizi kurang tetap pada angka 13,0%, kemudian naik menjadi 13,9% pada
tahun 2013 dan pada tahun 2018 prevalensi balita gizi kurang yaitu 13,8%. Hal ini menunjukkah
bahwa hampir tidak adanya penurunan prevalensi balita gizi kurang di Indonesia. Prevalensi balita
gizi kurang di provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 yaitu 9,3%, tahun 2017 meningkat
menjadi 10,2% dan tahun 2018 yaitu 12,3% 5,6,7,8
. Hal ini menunjukan prevalensi balita gizi
kurang di provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, angka
tersebut juga melebihi ambang batas suatu wilayah dengan kategori baik menurut WHO yaitu ≤
10%.
Salah satu kabupaten yang memiliki prevalensi gizi kurang di Provinsi Sumatera Selatan
yaitu Kabupaten Lahat dengan prevalensi 12,1%, angka tersebut mendekati angka prevalensi gizi
kurang di Provinsi Sumatera Selatan, hal ini juga menunjukan bahwa Kabupetan Lahat juga
memiliki prevalensi gizi kurang yang melebihi ambang batas suatu wilayah dengan kategori baik
menurut WHO9.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk masalah gizi kurang pada balita adalah dengan
pemberian makanan tambahan (PMT). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2011
melaksanakan kegiatan pemberian PMT Pemulihan dan PMT Penyuluhan di setiap puskesmas
untuk balita 6 - 59 bulan. PMT-P kemasan adalah biskuit dengan kandungan 10 vitamin dan 7
mineral. Biskuit ini diberikan pada balita selama 90 hari berturut-turut dan dikonsumsi sekali
setiap hari10
.
Theory of Planned Behavior (teori perilaku terencana) menjelaskan karena niat untuk
berperilaku maka muncul perilaku seseorang. Perilaku spesifik lebih ditekankan daripada perilaku
secara umum. Tiga hal yang dapat memprediksi niat seseorang dalam berperilaku yaitu sikap
terhadap perilaku (attitude toward the behavior) yang merupakan penilaian positif atau negatif
terhadap perilaku tertentu, norma subyektif (subjective norm) adalah kepercayaan terhadap orang
lain untuk mendukung atau tidak mendukung suatu perilaku tertentu sesuai dengan tuntutan, dan
persepsi pengendalian diri (perceived behavioral control) seseorang terhadap kemampuan untuk
menampilkan suatu perilaku tertentu11
. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberian
Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) pada balita gizi kurang dilihat dari Teori Perilaku
Terencana (TPB).
METODE
Penelitian survei analitik observasional dengan desain cross sectional. Populasi adalah ibu
balita gizi kurang dan tercatat di tiga puskesmas yang memiliki distribusi tetinggi biskuit PMT di
wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat yaitu Puskesmas Bandar Jaya, Puskesmas Pagar
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 240
Agung dan Puskesmas Perumnas. Sampel penelitian ini berjumlah 127 responden. Teknik sampel
yang digunakan adalah purposive sampling. Variabel Independen dan variabel dependen diukur
menggunakan kuesioner. Analisa data yang dilakukan adalah univariat dan bivariat. Analisis
dilakukan dengan uji statistik menggunakan uji Chi Square.
HASIL PENELITIAN
Hasil Univariat
Distribusi frekuensi karakteristik responden dan variabel sikap, norma subjektif, persepsi
pengendalian diri dan niat ibu dalam pemberian makanan tambahan pemulihan dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Umur Ibu Balita, Umur Balita dam Jenis Kelamin
Balita Gizi Kurang
Variabel Frekuensi Persentase
Umur Ibu
< 30 th 52 40,9
≥ 30 th 75 59,1
Umur Balita
6-11 bulan 20 15,7
12-59 bulan 107 84,3
Jenis kelamin Balita
Laki-laki 65 51,2
Perempuan 62 48,8
Sikap
Positif 87 68,5
Negatif 40 31,5
Norma Subjektif
Mendukung 30 23,6
Kurang mendukung 97 76,4
Persepsi Pengendalian Diri
Baik
Kurang baik
99
28
78,0
22,0
Niat
Kuat
Lemah
45
82
35,4
64,6
Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar ibu berusia diatas 30 tahun
yaitu 59,1%, sebagian besar anak berusia 12-59 bulan sebanyak 84,3% dengan jenis kelamin
terbanyak yaitu laki-laki 51,2%. Sebagian besar ibu memiliki sikap positif sebesar 68,5%, variabel
norma subjektif ibu kurang mendukung sebanyak 76,4 % sedangkan persepsi pengendalian diri ibu
yaitu perilaku ibu yang baik sebanyak 78,0%. Dari hasil penelitian didapat data bahwa sebagian
besar ibu mempunyai niat lemah dalam pemberian makanan tambahan pemulihan sebesar 64,6%.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 241
Analisis Bivariat
Berdasarkan distribusi data variabel sikap ibu, norma subjektif dan persepsi pengendalian diri
ibu sebagai variabel independen dengan niat ibu dalam pemberian makanan tambahan pemulihan
pada balita diperoleh tabulasi yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini :
Tabel 2.Analisis Sikap, Norma Subjektif dan Persepsi Pengendalian Diri dengan Niat Ibu
dalam Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan Balita Gizi Kurang
Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa proporsi ibu dengan sikap yang positif
dan memiliki niat kuat sebesar 46,0% sedangkan ibu dengan sikap yang negatif dan memiliki niat
kuat sebesar 12,5%. Hasil uji statistik didapat p-value < 0,05 (0,001) dengan kesimpulan tedapat
hubungan yang signifikan antara variabel sikap dan niat memberikan PMT-P pada balita gizi
kurang, proporsi ibu dengan norma subjektif mendukung yang memiliki niat kuat sebesar 80,0%
sedangkan ibu dengan norma subjektif kurang mendukung yang memiliki niat kuat sebesar
21,6%. Hasil uji statistik didapat p-value < 0,05 (<0,0001) dengan kesimpulan terdapat hubungan
signifikan antara norma subjektif dan niat memberikan PMT-P pada balita gizi kurang dan
proporsi persepsi pengendalian diri ibu yang baik dan melakukan niat kuat sebesar 40,4%
sedangkan persepsi pengendalian diri ibu yang kurang baik dan melakukan niat kuat sebesar
17,9%. Hasil uji statistik didapat p-value < 0,05 (0,048) dengan kesimpulan terdapat hubungan
yang signifikan antara variabel persepsi pengendalian diri ibu dengan niat memberikan PMT-P
pada balita gizi kurang.
PEMBAHASAN
Hubungan antara Sikap dengan Niat Ibu dalam Memberikan PMT-P
Berdasarkan model teori perilaku terencana, sikap sangat mempengaruhi niat ibu dalam
memberikan PMT-P pada balita gizi kurang. Sikap merupakan hasil dari akibat suatu perilaku
yang dilakukan atau tidak dilakukan pada tindakan tertentu12
. Dalam penelitian ini sikap ibu
dapat dilihat dari penilaian positif dan negatif ibu terhadap pemberian biskuit makanan tambahan
pada balitanya serta keyakinan ibu mengenai konsekuensi dari tindakan tersebut dengan berbagai
manfaat dan kerugian yang mungkin diperoleh setelah balitanya diberikan biskuit makanan
Variabel Niat
Kuat Lemah P-value PR (95% CI)
Sikap n % n % 3,678
Positif 40 46 47 54 0,001 (1,571-8,614)
Negatif 5 12,5 35 87,5
Norma Subjektif
Mendukung 24 80 6 20 <0,0001 3,695
Kurang Mendukung
21 21,6 76 78,4 (2,431-5,617)
Persepsi
Pengendalian
Diri
Baik 40 40,4 59 59 0,048 2,263
Kurang Baik 5 17,9 23 82,1 (0,987-5,187)
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 242
tambahan. Sikap terhadap perilaku memiliki pengaruh yang nyata dan merupakan faktor yang
paling besar berpengaruh pada niat seseorang13,14
.
Biskuit PMT Pemulihan mempunyai kandungan minimal 160 kalori, 3,2-4,8 gram
protein, dan 4-7,2 gram lemak untuk setiap 40 gram biskuit. Sasaran utama pemberian makanan
tambahan adalah balita kurus usia 6-59 bulan selama 90 hari15. PMT Pemulihan bertujuan
memenuhi kebutuhan energi dan protein balita gizi kurang sehingga jika diberikan secara tepat
maka dapat meningkatkan status gizi menjadi lebih baik16. Penyataan tersebut di setujui oleh
semua responden pada penelitian ini, mereka menilai bahwa biskuit makanan tambahan yang
diberikan pada balita bermanfaat pada status gizi anak.
Adanya hubungan sikap dan niat dalam memberikan PMT-P pada balita gizi kurang
terjadi karena ibu yang menganggap biskuit makanan tambahan mempunyai manfaat bagi
balitanya maka ibu tesebut akan memberikan respon positif sehingga mebentuk niat yang kuat
untuk memberikan biskuit makanan tambahan untuk balitanya dengan keinginan adanya
perubahan status gizi buruk menjadi status gizi baik, sebaliknya ibu yang menganggap biskuit
makanan tambahan tidak mempunyai manfaat bagi balitanya maka ibu tersebut akan memberikan
respon negatif sehingga niat ibu untuk memberikan biskuit makanan pada anaknya juga lemah.
Hubungan antara Norma Subjektif dengan Niat Ibu dalam Memberikan PMT-P
Norma subyektif (subjective norm) merupakan perilaku yang dilakukan atau tidak
dilakukan karena persepsi tekanan dari lingkungan. Subjective norm adalah kombinasi
kepercayaan seseorang mengenai setuju dan atau tidak setuju terhadap suatu perilaku (normative
beliefs)17
. PMT-Pemulihan dalam bentuk biskuit pabrikan yang diberikan pada balita untuk
memenuhi kebutuhan gizinya. Namun dari penelitian ini masih banyak ditemukan ibu balita yang
tidak memberikan makanan lainnya lagi setelah balita diberikan biskuit PMT-P karena
menganggap balita sudah kenyang setelah mengkonsumsi biskuit tersebut.
Salah satu kendala yang dihadapi dalam pemberian biskuit PMT-P pada balita adalah
rendahnya kesadaran ibu akan pentingnya mengkonsumsi makanan utama sehat dan gizi oleh
balita gizi kurang (biskuit PMT-P dijadikan sebagai makanan utama), sehingga menyebabkan
tidak ada kenaikan berat badan balita gizi kurang meskipun telah mengkonsumsi biskuit PMT-
Pemulihan. Dalam pemberian biskuit PMT-Pemulihan, biskuit tersebut seharusnya hanya
dikonsumsi oleh balita gizi kurang sebagai tambahan makanan sehari-hari bukan sebagai
makanan pengganti makanan utama18
. Untuk mendukung efektifitas biskuit PMT-P kepada balita
gizi kurang, maka peran ibu sangat penting dalam memberikan berbagai makanan yang beragam
untuk meningkatan status gizi balita. Karena sebagian besar ibu balita masih memberikan biskuit
PMT-P tersebut untuk dikonsumsi oleh anggota keluarga lainnya, sedangkan menurut petunjuk
teknis PMT-Pemulihan balita, setiap biskuit makanan tambahan yang diberikan harus dihabiskan
oleh balita gizi kurang yang menerima biksuit PMT-P19
.
Hasil penelitian ini menunjukan adanya hubungan antara norma subjetif dengan niat ibu
dalam memberikan PMT-P pada balita gizi. Hal ini terjadi karena ibu dengan normative beliefs
yang tinggi mempunyai kesadaran yang tinggi dalam memberikan biskuit makanan tambahan
pada balitanya dan norma subjektif ibu terbentuk dari lingkungan sosial yang mendukung
sehingga memotivasi ibu untuk memberikan biskuit makanan tambahan pada balita.
Hubungan antara Persepsi Pengendalian Diri dengan Niat Ibu dalam Memberikan PMT-P
Persepsi pengendalian diri merupakan fungsi berdasarkan control dari beliefs yaitu belief
seseorang tentang faktor pendukung atau penghambat dalam berprilaku. Kontrol terhadap prilaku
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 243
akan dirasakan lebih besar apabila seseorang merasakan adanya faktor pendukung yang lebih
banyak dibandingkan faktor penghambat, begitu juga sebaliknya11
. Hasil penelitian ini
menunjukan ada hubungan yang signifikan antara variabel persepsi pengendalian diri ibu dengan
niat ibu memberikan PMT-P pada balita gizi kurang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian
Ariwati, dkk yaitu terdapat hubungan persepsi kontrol perilaku ibu dengan niat dalam pemberian
ASI ekslusif pada bayi 6-12 bulan di Kabupaten Kelaten20
. Menurut Ajzen (2012) persepsi
pengendalian diri merupakan keyakinan individu terhadap factor yang mendukung dan
menghambat suatu tindakan. Persepi pengendalian diri ditentukan oleh pandangan seseorang
apakah sulit atau tidak dalam melakukan suatu tindakan tertentu21
.
Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Anggota keluarga lain yang ikut
mengkonsumsi biskuit makanan tambahan menjadi hambatan sebagian besar dari ibu balita yang
menjadi responden penelitian, sedangkan anak yang menyukai rasa biskuit PMT-Pemulihan
menjadi hal yang mempermudah ibu dalam memberikan biskuit PMT-P pada balitanya. Namun
ternyata tidak semua balita menyukai biscuit PMT-P, berdasarkan hasil penelitian Putri dan
Mahmudiono, 2020 bahwa sebanyak 73,7% balita tidak menghabiskan biscuit PMT-P yang
diberikan dengan alasan balita kurang menyukai rasa biscuit PMT-P yang diberikan karena
membuat enek dan sebagian lain menjawab balita bosan mengonsumsi PMT yang diberikan22
.
Adanya hubungan antara persepsi kontrol perilaku ibu dalam memberikan PMT-P
dikarenakan persepsi pengendalian diri ibu mempunyai implikasi motivasional terhadap niat. Ibu-
ibu balita yang percaya mereka tidak mempunyai kemudahan atau memiliki hambatan untuk
memberikan biskuit makanan tambahan akan berpeluang untuk tidak akan membentuk niat yang
kuat untuk melakukannya meskipun ibu-ibu balita tersebut mempunyai sikap yang positif
terhadap pemberian biskuit makanan tambahan untuk balitanya.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah niat ibu dalam pemberian biskuit makanan
tambahan dapat terbentuk dari sikap ibu yang postif, norma subjektif yang mendukung dan
persepsi pengendalian diri ibu yang baik dalam pemberian biskuit makanan tambahan pemulihan
pada balitanya.
Sarannya adalah meningkatkan edukasi pada ibu balita oleh puskesmas melalui
penyuluhan terkait prosedur pemberian biskuit makanan tambahan sesuai dengan yang
dianjurkan.
DAFTAR PUSTAKA
1. Patel, A., Badhoniya, N., Khadse, S., Senarath, U., Agho, K.E. and Dibley, M.J.
2006. Infant and Young Child Feeding Indicators and Deter-minants of Poor Feeding
Practices in India: Secondary Data Analysis of National Family Health Survey 2005–
06. Food and Nutrition Bulletin, 31(2)
2. Wong , D. L et al. (2010).Buku Ajar Keperawatan Pediatrik Volume 1. Edisi 6. Jakarta:
EGC
3. Skalicky, A., Meyers, A.F., Adams, W.G., Yang, Z., Cook, J.T. and Frank, D.A.
2006. Child Food Insecurity and Iron De! ciency Anemia in Low-Income Infants and
Toddlers in the United States.Maternal and Child Health Journal, 10(2)
4. Blossner M, de Onis M. Malnutrition quantifying the health impact at national
and local levels. Geneva: World Health Organization; 2005.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 244
5. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). (2007). Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan Kementerian RI tahun 2007.
6. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). (2010). Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan Kementerian RI tahun 2010.
7. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). (2013). Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan Kementerian RI tahun 2013.
8. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). (2018). Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan Kementerian RI tahun 2018.
9. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018. Palembang : Dinkes Prov. Sumsel
10. Kementerian Kesehatan RI. 2011. Panduan Penyelenggaraan Pemberian Makanan
Tambahan Pemulihan Bagi Balita Gizi Kurang. Jakarta
11. Ajzen, I., 1991. Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human
Decision Processes, Volume 50, pp. 179-211
12. Ajzen, I. (2005). Attitudes, Personality and Behavior, (2ndedition), Berkshire, UK: Open
University Press-Mc Graw Hill Education
13. Wikamorys, DA., Rochmach, TN. 2017. Aplikasi Theory Of Planned Behavior dalam
Membangkitkan Niat Pasien Untuk melakukan Operasi Katarak. Jurnal Administrasi
Kesehatan Indonesia Volume 5 Nomor 1 Januari - Juni 2017. 32-40
14. Haghighi, M., 2012. An Application of the Theory of Planned behavior (TBP) in
describing Customers‟ Use of Cash Cards in Points of Sale (POS). International Journal
of Learning and Development, 2 (6)
15. Kementerian Kesehatan RI. 2017. Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan
(Balita - Anak Sekolah - Ibu Hamil).
16. Adelasanti, A. N. & Rakhma, L. R. Hubungan Antara Kepatuhan Konsumsi Pemberian
Makanan Tambahan Balita dengan Perubahan Status Gizi Balita di Puskesmas
Pucangsawit Surakarta. J. Dunia Gizi1, 92–100 (2018)
17. Ajzen, I., 2006. Constructing a TPB Questionnaire : Conceptual and Methodological
Considerations. http://www.people.umass.edu
18. Rahma. (2016). Program Pemberian Makanan Tambahan untuk Peningkatan Status Gizi
Ibu Hamil dan Balita di Kecamatan Cilamaya Kulon dan Cilamaya Wetan , Karawang
(Complementary Foods Giving Program to Increase Nutritional Status of Pregnant
Women and Infants in Cilamaya K. Jurnal CARE Jurnal Resolusi Konflik, CSR, dan
Pemberdayaan Juni 2016, Vol. 1 (1): 44-49 ISSN: 2528-0848, 1(1), 44–49.
19. Kementrian Kesehatan RI. 2011. Makanan Sehat Untuk Bayi. Jakarta : Kementrian
Kesehatan RI
20. Ariwati, V. D., Tamtomo, D., & Sulaeman, E. S. (2016). Path Analysis on the
Effectiveness of Exclusive Breastfeeding Advocacy Program on Breastfeeding Practice
using Theory of Planned Behavior. Journal of Health Promotion and Behavior, 01(03),
149–159. https://doi.org/10.26911/thejhpb.2016.01.03.02
21. Ajzen, Icek. (2012). ―The Theory of Planned Behavior. In P. A. M. Lange, A. W.
Kruglanski & E. T.Higgins (Eds.)‖. Handbook of Theories of Social psychology(Vol. 1,
pp. 438-459). London, UK: Sage
22. Putri, ASR,. Mahmudiono.T., 2020. Efektivitas Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
Pemulihan Pada Status Gizi Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Simomulyo, Surabaya
Amerta Nutr (2020).58-64
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 245
PROFIL TAHAPAN ANEMIA DEFISIENSI BESI PADA ANAK SEKOLAH
DASAR
DI DAERAH PEDESAAN: STUDI CROSS SECTIONAL DI KECAMATAN
TUAH NEGERI KABUPATEN MUSI RAWAS
Rostika Flora1*
, Mohammad Zulkarnain2, Nur Alam Fajar
1, Achmad Fickry Faisa
3, Indah
Yuliana4, Nurlaili
5, Ikhsan
5, Samwilson Slamet
5, Risnawati Tanjung
6, Aguscik
7
1Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya
2Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran,Universitas Sriwijaya
3Prodi Ilmu Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya
4Prodi Ilmu Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya
5Prodi D-III Keperawatan, Fakultas Matematika& Ilmu Pengetahuan Alam,Universitas Bengkulu
6Prodi Kesehatan Lingkungan, Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan, Medan
7Prodi Keperawatan, Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan, Palembang
Jl. Palembang Prabumulih Km.32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan
*Corresponding email : [email protected]
PROFILE STAGES OF IRON DEFICIENCY ANEMIA IN ELEMENTARY SCHOOL
CHILDREN IN RURAL AREA: A CROSS SECTIONAL STUDY IN SUB DISTRICT
TUAH NEGERI, DISTRICT MUSI RAWAS
ABSTRACT
Background: Elementary school children are considered vulnerable group to have iron deficiency anemia,
because of the high needs for iron during their growing period. Insufficient iron consumption and low iron
absorption are the main causes of iron deficiency anemia. This condition is more common in rural areas.
Rural areas are commonly related to the limited availability of health facilities and food. This study aims to
determine the profile of the stages of iron deficiency anemia in elementary school children in rural areas in
Kecamatan Tuah Negeri. Methods: The study design was cross sectional, with samples of 7-12 years old
elementary school children in Kecamatan Tuah Negeri. The total sample is 91 children that were taken
randomly. Hb levels, Fe serum levels, TIBC levels and transferrin saturation were examined, while the
characteristic data from the samples were obtained through a questionnaire. The stages of iron deficiency
anemia are classified into 3 stages. After that, the obtained data were analyzed with univariate analysis.
Results: the results of the hematological examination showed that most of the children had low Hb levels
(52.7%), 48.3% had Fe serum level <40 µg / dL and 27.5% had TIBC levels > 390 µg / dL and 28.6% had
transferrin saturation <10%. Based on the stages of deficiency anemia, it was found that 15.4% of children
had anemia without iron deficiency, 33% of children had iron deficiency, 37.4% of children had iron
deficiency anemia and only 14.3% of children were normal. Conclusion: iron deficiency and low levels of
Hb increase the incidence of iron deficiency anemia in elementary school children in Tuah Negeri, Musi
Rawas Regency.
Keywords: iron, iron deficiency anemia, elementary school children
ABSTRAK
Latar belakang: Anak sekolah dasar dianggap sebagai kelompok yang rentan mengalami anemia defisiensi
besi, karena tingginya kebutuhan zat besi pada masa pertumbuhan. Konsumsi zat besi yang tidak cukup dan
absorbsi zat besi yang rendah menjadi penyebab utama anemia defisiensi besi. Kondisi ini lebih sering
terjadi di daerah pedesaan. Wilayah pedesaan berkaitan dengan terbatasnya ketersediaan fasilitas kesehatan
maupun ketersediaan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil tahapan anemia defisiensi besi
pada anak sekolah dasar di daerah pedesaan, Kecamatan Tuah Negeri. Metode: Desain penelitian ini adalah
cross sectional, dengan sampel anak Sekolah Dasar di Kecamatan Tuah Negeri berusia 7-12 tahun. Sampel
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 246
berjumlah 91 orang yang diambil secara random. Dilakukan pemeriksaan kadar Hb, kadar Fe serum dan
kadar TIBC serta saturasi transferin, sedangkan data karakteristik sampel diperoleh melalui kuesioner.
Tahapan anemia defisiensi besi dikelompokkan menjadi 3 tahapan. Selanjutnya data yang diperoleh
dianalisis secra univariate. Hasil: hasil pemeriksaan hematologi menunjukkan bahwa, sebagian besar anak
mempunyai kadar Hb yang rendah (52.7%), 48.3% anak mempunyai kadar Fe serum < 40 µg/dL dan 27.5%
anak mempunyai kadar TIBC >390 µg/dL serta 28,6% anak mempunyai saturasi transferin < 10%.
Berdasarkan tahapan anemia defisiensi diperoleh bahwa 15.4% anak mengalami anemia tanpa disertai
defisiensi zat besi, 33% anak mengalami defisiensi besi, 37,4% anak mengalami anemia defisiensi besi dan
hanya 14.3% anak yang normal. Kesimpulan: defisiensi besi dan rendahnya kadar Hb meningkatkan angka
kejadian anemia defisiensi besi pada anak sekolah dasar di kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas.
Kata Kunci: zat besi, anemia defisiensi besi, anak sekolah dasar
PENDAHULUAN
Anemia defisiensi besi merupakan masalah kesehatan yang umum terjadi di negara
berkembang. Anemia defisiensi besi terjadi Anemia defisiensi besi terjadi karena terbatasnya
persediaan zat besi untuk pembentukan eritrosis yang berdampak terhadap penurunan kadar
hemoglobin. Anak sekolah dasar dianggap sebagai kelompok yang rentan mengalami anemia
defisiensi besi dikarenakan tingginya kebutuhan zat besi pada masa pertumbuhan.1 Menurut WHO
(2008), 48% anak usia 5-14 tahun di negara berkembang mengalami anemia.2 Sementara data
Riskesdas (2013) menyebutkan, prevalensi anemia defisiensi besi di Indonesia pada anak kelompok
usia 5-12 tahun sebesar 29%. Prevalensi ini lebih tinggi dibandingkan prevalensi pada kelompok
balita (28,1%) dan wanita usia subur(23,9%).3
Prevalensi anemia yang tinggi pada anak sekolah akan berdampak terhadap penurunan
konsentrasi,prestasi belajar dan kebugaran jasmani. Defisiensi zat besi baik yang disertai dengan
adanya anemia ataupun tanpa disertai anemia, akan berpengaruh terhadap perkembangan kognitif
anak. Zat besi merupakan salah satu mikronutrien penting yang berperan terhadap proses
perkembangan otak, yaitu pada proses mielinisasi, metabolisme neuron, dan proses di
neurotransmitter. 4
Oleh karena itu, defisiensi zat besi akan mengakibatkan penurunan sitokrom
dalam mitokondria yang akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan, bahkan abnormalitas
pertumbuhan termasuk di dalamnya adalah kecerdasan intelektual.5 Beberapa penelitian
menyebutkan, anemia defisensi besi mengakibatkan gangguan pada fungsi kognitif yang berkaitan
dengan rendahnya konsentrasi dan pemahaman konsep pada anak.6,7,8
Kurangnya konsumsi zat besi, dan rendahnya absorbsi zat besi serta pola makan yang
sebagian besar terdiri dari nasi dengan menu yang tidak bervariasi menjadi penyebab utama anemia
defisiensi besi pada anak. Kondisi ini lebih sering terjadi di daerah pedesaan. Menurut Hu et al
(2014) wilayah perkotaan dan perdesaan berpengaruh terhadap suatu masalah gizi melalui
mekanisme yang berhubungan dengan ketersediaan fasilitas kesehatan maupun ketersediaan
makanan.9
Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan.
Angka gizi buruk (42 anak, tahun 2016) di Kabupaten ini masih cukup tinggi.10
Gizi buruk erat
kaitannya dengan kejadian anemia defisiensi besi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil
anemia defisiensi besi pada anak sekolah dasar di daerah pedesaan di Kabupaten Musi Rawas,
yaitu Kecamatan Tuah Negeri.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 247
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional yang dilakukan terhadap anak sekolah
dasar di Kecamatan Tuah Negeri. Sampel berjumlah 91 orang yang merupakan anak sekolah dasar
usia 7-13 tahun yang diambil secara random. Dilakukan pengambilan darah di vena cubitii untuk
pemeriksaan kadar Hb, kadar Fe serum dan kadar TIBC. Data saturasi transferin diperoleh dengan
menggunakan rumus: (kadar Fe serum / TIBC) x 100%, sedangkan data karakteristik sampel
diperoleh melalui kuesioner. Penentuan anemia defisiensi besi berdasarkan hasil pemeriksaan
kadar Hb, kadar Fe serum dan kadar TIBC serta saturasi transferin. Kadar Hb dikategorikan
menjadi 2 yaitu normal ≥ 12 gr/dL dan anemia < 12 gr/dL; kadar Fe serum kategorikan menjadi 3
yaitu Tahap 1 (normal), Tahap II (<60 µg/dL), Tahap III (<40 µg/dL); kadar TIBC dikategorkan
menjadi 3 yaitu Tahap I (360-390 µg/dL), Tahap II (>390 µg/dL), Tahap III (> 410 µg/dL);
saturasi transferin dikategorikan menjadi III yaitu Tahap 1 (20-30%), Tahap II (<15%), Tahap III
(<10%). Tahapan anemia defisiensi besi dikategorikan menjadi Tahap 1 (normal); Tahap II
(defisiensi besi) dan Tahap III (anemia defisiensi besi). Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan
dipresentasikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Penelitian ini telah mendapat persetujuan etik
dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan FKM Unsri dengan No. 150/UN9.1.10/KKE/2020.
HASIL
Berdasarkan data karakteristik anak (Tabel 1) didapatkan bahwa, sebagian besar anak
berusia > 9 – 12 tahun dan berjenis kelamin perempuan (59.3%). Data karakteristik orang tua
diperoleh sebagian besar ibu (67%) dan ayah (70%) berpendidikan rendah, 42.9% ibu bekerja,
93.4% ayah bekerja dan 86.8% mempunyai status ekonomi rendah.
Tabel 1. Karakteristik Anak Sekolah Dasar di Kecamatan Tuah Negeri
Berdasarkan hasil pemeriksaan hematologi (Tabel 2) didapatkan bahwa, sebagian besar
anak mempunyai kadar Hb rendah (52.7%), 48.3% anak mempunyai kadar Fe serum < 40 µg/dL
dan 27.5% anak mempunyai kadar TIBC >390 µg/dL serta 28,6% anak mempunyai saturasi
transferin < 10%.
Distribusi Frekuensi n %
1. Usia
a. 7 – 9 tahun
b. > 9 – 12 tahun
40
51
43.9
56.1
2. Jenis Kelamin
a. Laki- Laki
b. Perempuan
37
54
40.7
59.3
3. Pendidikan Ibu
a. Rendah
b. Tinggi
61
30
67.0
33.0
4. Pekerjaan Ibu
a. Bekerja (Petani)
b. Tidak bekerja
39
52
42.9
57.1
5. Pendidikan ayah
a. Rendah
b. Tinggi
64
27
70.0
30.0
6. Pekerjaan Ayah
a. Bekerja (Petani)
b. Bukan petani
85
6
93.4
6.6
7. Status Ekonomi
a. Rendah
b. Tinggi
79 12
86.8 13.2
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 248
Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Hematologi Berdasarkan Tahapan Defisiensi Besi
Grafik 1. Profil Anemia Defisiensi Besi Pada Anak Sekolah Dasar
Berdasarkan hasil pemeriksaan hematologi (Tabel 2), diperoleh sebaran tahapan anemia
defisiensi pada anak sekolah dasar (Grafik 1) yaitu 15.4% anak mengalami anemia tanpa disertai
defisiensi zat besi, 33% anak mengalami defisiensi besi, 37,4% anak mengalami anemia defisiensi
besi dan hanya 14.3% anak yang tidak mengalami anemia, defisiensi besi maupun anemia
defisiensi besi.
PEMBAHASAN
Gambaran hasil hematologi (Tabel 2) pada penelitian ini menunjukkan bahwa, sebagian
besar anak mempunyai kadar Hb yang rendah (52.7%). Hal ini menunjukkan sebagian besar anak
mengalami anemia. Menurut WHO (2008), sebagian besar anak sekolah di seluruh dunia
mengalami anemia.2 Di Indonesia prevalensi anemia pada anak sekolah masih menunjukkan angka
yang cukup tinggi. Rendahnya asupan zat besi, masa pertumbuhan dan aktifitas fisik yang tinggi
mengakibatkan anak sekolah rentan terhadap kejadian anemia. Anemia yang paling sering terjadi
pada anak sekolah adalah anemia yang disebabkan oleh defisiensi besi.11
0
10
20
30
40
Anemia Defisiensi besi Anemia Defisiensibesi
Normal
Per
sen
tase
(%
)
Tahapan Defisiensi Besi
Distribusi Frekuensi n %
1. Kadar Hemoglobin
a. Normal b. Rendah
43 48
47.3 52.7
2. Kadar Fe Serum
a. Tahap 1 (Normal)
b.Tahap 2 c. Tahap 3
27
20 44
29.7
22.0 48.3
3. Kadar TIBC
a. Tahap 1 (Normal)
b. Tahap 2 c. Tahap 3
37
19 35
51.6
27.5 20.9
4. 4. Saturasi Transferin
5. a. Tahap 1 (Normal)
6. b. Tahap 2 7. c. Tahap 3
41
24 26
45.0
26.4 28.6
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 249
Hasil pengukuran kadar zat besi pada penelitian ini menunjukkan bahwa, 68,3 % anak
mempunyai kadar Fe serum yang rendah. Rendahnya asupan zat besi dan masalah kemiskinan
terutama di pedesaan menjadi faktor yang berperan terhadap tingginya angka anemia defisiensi
besi.11
Data Riskesdas (2013) menunjukkan menunjukkan anemia defisiensi besi pada anak usia 5-
12 tahun sebesar 29%, dengan prevalensi di pedesaan sebesar 31%.3 Terbatasnya jenis pekerjaan
dan rendahnya pendapatan di pedesaan berpengaruh terhadap tingginya defisiensi besi pada anak.
Data karakteristik anak (Tabel 1) menunjukkan bahwa hampir keseluruhan orang tua bekerja
sebagai petani dan 86.8% orang tua berpenghasilan rendah. Penghasilan berpengaruh terhadap
kemampuan daya beli pangan dari keluarga dalam memenuhi kebutuhan asupan zat gizi keluarga.
Oleh karena itu, rendahnya penghasilan orang tua juga akan bepengaruh terhadap pemenuhan zat
gizi anak, termasuk pemenuhan makanan sumber zat besi. Selain itu asupan zat besi yang rendah
juga dapat dikarenakan pada anak usia sekolah merupakan usia dimana anak sangat aktif bermain
dan mengalami penurunan nafsu makan, sehingga konsumsi makanan dan asupan zat besi menjadi
tidak seimbang dengan kebutuhan zat besi yang diperlukan.12
Menurut World Health Organization
(2008), defisiensi zat besi merupakan salah satu dari sepuluh masalah kesehatan yang paling
serius.2
Adanya defisiensi besi yang disertai dengan penurunan kadar hemoglobin meningkatkan
angka kejadian anemia defisiensi besi pada anak. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar
anak mempunyai kadar Hb yang rendah (52.7%), 48.3% anak mempunyai kadar Fe serum < 40
µg/dL dan 27.5% anak mempunyai kadar TIBC >390 µg/dL serta 28,6% anak mempunyai saturasi
transferin < 10%. (Tabel 2). Berdasarkan pengukuran hematologi tersebut, didapatkan 37,4% anak
mengalami anemia defisiensi besi (Grafik 1). Anemia Defisiensi besi adalah anemia yang terjadi
akibat kekurangan zat besi dalam darah, artinya konsentrasi hemoglobin dalam darah berkurang
karena terganggunya pembentukan sel-sel darah merah akibat kurangnya kadar zat besi dalam
darah. Jika simpanan zat besi dalam tubuh seseorang sudah sangat rendah berarti orang tersebut
mendekati anemia walaupun belum ditemukan gejala-gejala fisiologis. Simpanan zat besi yang
sangat rendah lambat laun tidak akan cukup untuk membentuk selsel darah merah di dalam
sumsum tulang sehingga kadar hemoglobin terus menurun di bawah batas normal, keadaan inilah
yang disebut anemia defisiensi besi.13
Prevalensi anemia defisiensi besi pada anak sekolah di Indonesia masih menunjukkan angka
yang cukup tinggi. Data Riskesdas (2013) menyebutkan 29% anak usia sekolah di Indonesia
menglami anemia defisiensi besi dengan prevalensi di pedesaan sebesar 31%.3 Menurut Khumaidi
(1989) tingginya prevalensi anemia defisiensi besi di negara berkembang adalah keadaan sosial
ekonomi yang rendah meliputi pendidikan orang tua dan penghasilan yang rendah serta kesehatan
pribadi di lingkungan yang buruk. Meskipun anemia disebabkan oleh berbagai faktor, namun lebih
dari 50 % kasus anemia yang terbanyak diseluruh dunia secara langsung disebabkan oleh
kurangnya asupan zat besi.14
Kurangnya asupan zat besi dapat menimbulkan gangguan atau
hambatan pada pertumbuhan, baik sel tubuh maupun sel otak, sementara rendahnya kadar Hb dapat
menimbulkan gejala lesu, lemah, letih, lelah dan cepat lupa. Rendahnya kadar Hb akan
menyebabkan transpor oksigen menjadi berkurang dan mengakibatkan produksi energi menjadi
rendah sehingga anak menjadi mudah lelah dan kurang dapat berkonsentrasi.15
Hal ini akan
menurunkan prestasi belajar, kebugaran jasmani, produktifitas kerja serta menurunkan daya tahan
tubuh anak.13
KESIMPULAN
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 250
Defisiensi besi dan rendahnya kadar hemoglobin meningkatkan angka kejadian anemia
defisiensi besi pada anak sekolah dasar di kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas
UCAPAN TERIMAKASIH
Peneliti mengucapkan terimakasih atas didanainya penelitian ini dari hibah penelitian
Kementrian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi skim hibah Penelitian Dasar Tahun 2020,
No. Kontrak 0125.07/UN9/SB3.LP2M.PT/2020 dengan Dr. Rostika Flora sebagi Ketua Peneliti.
DAFTAR PUSTAKA
1. Naufal SN, Mulatsih S, Triasih S (Ed). 2005. Anemia Defisiensi Besi: Bioavailibilitas Zat
Besi. Yogyakarta: Medika Fakultas Kedokteran UGM
2. WHO. Worldwide prevalence of anemia 1993 – 2005, WHO global database on anaemia.
Geneva: WHO library cataloguing-in-publication data; 2008
3. Kemenkes RI. 2013. Riset Kesehatan Dasar; RISKESDAS. Jakarta: Balitbang Kemenkes RI.
4. McCann JC, Ames BN. An overview of evidence for a causal relation between iron
deficiency during development and deficits in cognitive or behavioral function. Am J Clin
Nutr. 2007 Apr;85(4):931-45.
5. Goudarzi, A & Mehrabi, M.R. & Goodarzi, Kourosh. (2008). The Effect of Iron Deficiency
Anemia on Intelligence Quotient (IQ) in under 17 Years Old Students. Pakistan journal of
biological sciences: PJBS. 11. 1398-400. 10.3923/pjbs.2008.1398.1400.
6. Doom, J.R.; Gunnar, M.R.; Georgieff, M.K.; Kroupina, M.G.; Frenn, K.; Fuglestad, A.J.
Beyond stimulus deprivation: Iron deficiency and cognitive deficits in postinstitutionalized
children. Child Dev. 2014, 85, 1805–1812
7. Carter, R.C.; Jacobson, J.L.; Burden, M.J.; Armony-Sivan, R.; Dodge, N.C.; Angelilli, M.L.;
Lozoff, B.; Jacobson, S.W. Iron deficiency anemia and cognitive function in infancy.
Pediatrics 2010, 126, e427–e434.
8. Geng F, Mai X, Zhan J, Xu L, Zhao Z, Georgieff M, et al. Impact of fetal-neonatal iron
deficiency on recognition memory at 2 months of age. J Pediatr. 2015;167:1226–32.
9. Hu et al, 2014, Disparity of anemia prevalence and associated factors among rural to urban
migrant and the local children under two years old: a population based crosssectional study in
Pinghu, China. BMC Public Health 2014.
10. Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan. Profil Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan.
2017. Palembang.
11. Bekele G, Wondimagegn A, Yaregal A, Lealem G. Anemia and Associated Factors Among
School-Age Children in Filtu Town, Somali Region, Southeast Ethiopia. BMC Hematol.
2014;14(7):9511-9528.
12. Notoatmodjo, S. 2003. Ilmu Kesehatan Masyarakat Prinsip-Prinsip Dasar. PT. Rineka Cipta.
Jakarta.
13. Masrizal. (2007). Anemia defisiensi besi. Jurnal Kesehatan Masyarakat, II(1), 140–145
14. Khumaidi, M., 1989. Gizi Masyarakat. Pusat Antar Universitas Pangan & Gizi IPB, Bogor
15. Sudargo, T, Kusmayanti, N.A dan Hidayanti N.L. 2014. Defisiensi Yodium, Zat Besi, dan
Kecerdasan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 251
ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN KATARAK DI INDONESIA
Bima Andika Persada,
1 Feranita Utama
2
1Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya
2Bagian Epidemiologi dan Biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya
Jl. Palembang Prabumulih KM. 32, Indralaya Indah Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan
Corresponding email: [email protected]
RISK FACTOR ANALYSIS OF CATARACTS IN INDONESIA
ABSTRACT
Cataract is one of the main causes of blindness in Indonesia. The results of Basic Health Research showed
an increase in the prevalence of cataracts in Indonesia from 1.3% in 2007 to 1.8% in 2013. The purpose of
this study was to determine the risk factors that affect the incidence of cataracts in Indonesia. This study
analyzed the secondary data of IFLS 2014 with a cross sectional design. The sample in this study was a
sample of all individuals aged > 40 years who were successfully interviewed in the survey and met the
inclusion and exclusion criteria of the study. This study conducted univariate, bivariate and multivariate
analysis. The results showed that there was a significant relationship between gender (p = 0.048), age (p =
<0.001), education (p = 0.008), type of area (p = 0.041), hypertension (p = <0.001), diabetes ( p = <0.001)
and glaucoma (p = <0.001) with the incidence of cataracts, and it can be concluded that the most dominant
risk factor for cataract incidence in Indonesia is glaucoma. To reduce the risk of cataracts, it is advisable to
reduce the use of eye drops, people over 40 years of age should carry out routine eye health checks and for
workers outside the building are advised to use personal protective equipment so that their eyes avoid direct
sun exposure.
Keywords: IFLS, Glaucoma, Cataract
ABSTRAK
Katarak merupakan salah satu penyebab utama kebutaan di Indonesia. Hasil Riset Kesehatan Dasar
menunjukkan peningkatan prevalensi katarak di Indonesia dari 1,3% pada tahun 2007 menjadi 1,8% pada
tahun 2013. Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui faktor risiko yang mempengaruhi kejadian katarak
di Indonesia. Penelitian ini menganalisis data sekunder IFLS 2014 dengan desain cross sectional. Sampel
dalam penelitian ini adalah sampel seluruh individu usia > 40 tahun yang berhasil diwawancarai dalam
survey, serta memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi penelitian. Penelitian ini melakukan analisis univariat,
bivariat dan multivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jenis
kelamin (p = 0,048 ), umur (p = <0,001), pendidikan (p = 0,008 ), tipe daerah (p = 0,041), hipertensi (p =
<0,001), diabetes (p = <0,001) dan glaukoma (p = <0,001) dengan kejadian katarak, dan dapat disimpulkan
bahwa faktor risiko paling dominan terhadap kejadian katarak di Indonesia adalah glaukoma. Untuk
mengurangi risiko katarak disarankan untuk mengurangi penggunaan tetes mata, masyarakat usia di atas 40
tahun sebaiknya melakukan pemeriksaan kesehatan mata secara rutin dan bagi pekerja di luar gedung
disarankan untuk menggunakan alat pelindung diri agar mata terhindar paparan sinar matahari langsung.
Kata Kunci: IFLS, Glaukoma, Katarak
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 252
PENDAHULUAN
Katarak merupakan suatu keadaan dimana lensa mata mengalami kekeruhan yang dapat
terjadi akibat hidrasi (penambahan cairan) lensa, denaturasi protein lensa atau diakibatkan oleh
kedua.1 Proses degenerasi terkait usia merupakan penyebab utama penyakit ini.
2 Faktor yang dapat
mempengaruhi kejadian katarak antara lain jenis kelamin, umur, rokok, konsumsi alkohol, paparan
sinar matahari, traumatik, pekerjaan, ekonomi, serta riwayat penyakit sistemik seperti diabetes
mellitus.1,3
Penyakit hipertensi juga merupakan faktor risiko dari penyakit katarak.4 Seiring
bertambahnya usia protein pada lensa mata akan semakin menurun, sehingga usia menjadi
penyebab yang paling sering menyebabkan katarak.5
Satu orang di dunia menderita kebutaan setiap 5 detik, dan WHO memperkirakan terdapat
lebih dari 7 juta orang menjadi buta setiap tahun. Sekitar 0,58% atau 39 juta orang menderita
kebutaan dan 82% dari penyandang kebutaan berusia 50 tahun atau lebih, 51% kebutaan di dunia
disebabkan oleh katarak6 dan angka ini diperkirakan akan meningkat 40 juta pada tahun 2020.
7
Gangguan penglihatan kedua di dunia dengan angka kejadian sebesar 33% juga disebabkan oleh
katarak.8 Penyakit katarak cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan telah
menyebar ke seluruh dunia. Di Amerika Serikat terdapat 10% orang mengalami katarak.9
Katarak paling di banyak terjadi di negara yang sedang berkembang seperti Asia dan Afrika. Negara
ini 10 kali lebih besar mengalami katarak dibandingkan dengan penduduk di negara maju. Saat ini
beberapa negara seperti di India katarak telah banyak menyerang usia produktif (prevalensi katarak
sebesar 24% pada kelompok 50-60 tahun, dan sebesar 16% berada di kelompok 30-50 tahun), di
Afrika sebesar 23,5% katarak terjadi pada kelompok usia 70 tahun dan 2,4% berada di kelompok
usia 40-49 tahun. Hasil Survei Kesehatan Indra Penglihatan Departemen Kesehatan Indonesia
Tahun 1993-1996, menunjukkan prevalensi katarak 33,4% pada kelompok umur antara 55-64, dan
62,2% pada kelompok umur 65 tahun ke atas. Data Surkesnas menunjukkan prevalensi katarak
1,6% pada umur produktif 40-54 tahun.10
Angka kebutaan di Indonesia menempati urutan pertama di Asia, sedangkan di dunia
Indonesia menempati urutan kedua setelah Ethiopia dengan angka prevalensi di atas 1%.4 WHO
menetapkan batas maksimal angka kebutaan di suatu negara adalah 0,5%. Bila prevalensi kebutaan
di suatu negara menunjukkan angka di atas 1% ini menandakan bahwa terdapat keterlibatan
masalah sosial/lintas sektor.7 Rata-rata angka kebutaan di Indonesia untuk penduduk di atas usia 50
tahun berdasarkan Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) adalah 3%, dengan
penyebab utama katarak. Indonesia juga menempati urutan tertinggi paling banyak penderita
katarak di Asia Tenggara.
Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 dan 2013, menunjukkan peningkatan prevalensi
katarak di Indonesia dari 1,3% pada tahun 2007 menjadi 1,8% pada tahun 2013. Insidensi katarak
diperkirakan sebesar 0,1% per tahun. Penduduk Indonesia cenderungan lebih cepat 15 tahun untuk
menderita katarak bila dibandingkan penduduk di daerah subtropis.11
Permasalahan katakrak perlu
segera di atasi agar tidak berlanjut menjadi peningkatan angka kebutaan, terutama di Indonesia
yang telah menjadi masalah kesehatan masyarakat dan dininy usia awal mengalami katarak. Untuk
itu perlu diteliti faktor risiko kejadian katarak dengan memanfaatkan data sekuder yang ada.
METODE
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional menggunakan
data sekunder IFLS tahun 2014. Metode pengambilan sampel dengan multistage random sampling.
Sampel yang digunakan berjumlah 13.806 responden yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 253
Analisis yang dilakukan menggunakan complex sample. Pada analisis bivariat menggunakan uji
chi-square dan analisis multivariat menggunakan uji regresi logistik berganda.
HASIL PENELITIAN Analisis Univariat
Berdasarkan data dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) 2014, didapatkan informasi
mengenai kejadian katarak pada penduduk usia ≥ 40 tahun di Indonesia. Adapun hasil univariat
disajikan dalam tabel 1:
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan
Variabel Penelitian
Variabel Total Responden
n %
Variabel Dependen
Katarak
Ya 629 4,6%
Tidak 13.177 95,4%
Variabel Independen
Usia
>50 tahun 7.406 53,6%
<50 tahun 6.400 46,4%
Jenis Kelamin Perempuan 7.288 52,8%
Laki-Laki 6.518 47,2%
Pendidikan
Rendah 10.161 73,6% Tinggi 3.645 26,4%
Tipe Daerah
Perdesaan 6.650 48,2%
Perkotaan 7.146 51,8%
Status Merokok
Perokok 3.880 40,8
Mantan Perokok 258 2,7
Bukan Perokok 5.364 56,5
Riwayat Diabetes
Diabetes 648 4,7%
Tidak Diabetes 13.158 95,3%
Riwayat Hipertensi Hipertensi 2.995 21,7%
Tidak Hipertensi 10.811 78,3%
Riwayat Glaukoma
Glaukoma 110 0,8% Tidak Glaukoma 13.695 99,2%
Tabel 1 menunjukkan dari 13.806 responden terdapat 4,6% penderita katarak di Indonesia.
Mayoritas responden berada pada > 50 tahun (53,6%), jenis kelamin perempuan (52,8%),
pendidikan tinggi (73,6%), tidak merokok (63,1%), tinggal di kota (51,8%), tidak diabetes (95,3%),
tidak hipertensi (78,3%), dan tidak glaukoma (99,2%).
Analisis Bivariat
Analisis bivariat dilakukan dengan tujuan untuk melihat hubungan variabel dependen yaitu
katarak dan variabel independen yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan, tipe daerah, status
merokok, riwayat diabetes riwayat hipertensi, riwayat glaukoma. Hasil analisis bivariat disajikan
dalam tabel dengan menampilkan nilai p-value, Prevalence Risk (PR), dan Confidence Interval (CI)
dari masing-masing variable pada tabel 2.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 254
Tabel 2. Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Katarak di Indonesia
Variabel
Katarak
p-value PR
(95% CI) Ya Tidak
n % n %
Usia ≥ 40 tahun 505 6,8 6.901 93,2 < 0,001 3,498
< 40 tahun 125 1,9 6.275 98,1 (2,983-4,102)
Jenis Kelamin
Perempuan 362 5 6.926 95 0,001 1,214 Laki-Laki 267 4,1 6.251 95,9 (1,080-1,365)
Pendidikan
Rendah 512 5 9.648 95 < 0,001 1,575
Tinggi 117 3,2 3.528 96,8 (1,336-1,858)
Tipe Daerah
Perdesaan 275 4,1 6.385 95,9 0,018 0,831
Perkotaan 355 5 6.791 95 (0,713-0,969)
Status Merokok
Merokok 216 4,2 4.876 95,8 0,062
0,894
(0,794-1,006) Tidak Merokok 413 4,7 8301 95,3
Riwayat Diabetes
Diabetes 74 11,5 574 88,5 <0,001 2,721 Tidak Diabetes 555 4,2 12.603 95,8 (2,300-3,220)
Riwayat Hipertensi
Hipertensi 219 7,3 2.776 92,7 <0,001 1,932
Tidak Hipertensi 410 3,8 10.401 96,2 (1,715-2,175) Riwayat Glaukoma
Glaukoma 45 40,8 65 59,2 <0,001 9,572
Tidak Glaukoma 584 4,3 13.112 95,7 (7,921-11,569)
Tabel 2 menunjukkan terdapat 6 variabel yang berhubungan (p-value < 0,05) dengan
kejadian katarak yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan, tipe daerah, status merokok, diabetes,
hipertensi dan glaukoma.
Analisis Multivariat
Setelah melakukan analisis bivariat, langkah selanjutnya pada tahap analisis multivariat
adalah menganalisis hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis
dilakukan menggunakan uji regresi logistik pada complex samples dengan memperhatikan strata,
cluster, dan bobot yang sudah dinormalisasi. Hasil analisis multivariat disajikan dalam tabel 3.
Tabel 3. Hasil Pemodelan Akhir Multivariat (Final Model)
Variabel p-value PRAdjusted
95% CI
Lower Upper
Usia <0,001 3,134 2,644 3,716 Jenis Kelamin 0,048 1,203 1,001 1,446
Pendidikan 0,008 1,277 1,067 1,528
Tipe Daerah 0,041 0,846 0,721 0,993
Status Merokok 0,414 1,080 0,897 1,300 Riwayat Diabetes <0,001 1,884 1,565 2,268
Riwayat Hipertensi <0,001 1,505 1,325 1,709
Riwayat Glaukoma <0,001 11,288 8,160 15,616
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 255
Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa faktor yang paling dominan adalah
glaukoma. Glaukoma dapat meningkatkan risiko terjadinya katarak di Indonesia sebesar 11,288
kali lebih besar dibandingkan tidak glaukoma (p-value = < 0,001; PRAdjusted = 11,288; 95% CI =
8,160-15,616).
PEMBAHASAN Usia
Hasil penelitian didapatkan bahwa yang mengalami kejadian katarak lebih banyak pada
kelompok usia > 50 tahun (6,8%) daripada yang berusia ≤ 50 tahun (1,9%). Uji statistik
menunjukkan bahwa individu yang berada pada kelompok usia > 50 tahun mempunyai peluang
3,134 kali lebih besar untuk mengalami kejadian katarak dibandingkan dengan individu yang
berusia ≤ 50 tahun setelah dikontrol oleh variabel glaukoma, riwayat diabetes, riwayat hipertensi,
pendidikan, tipe daerah, dan jenis kelamin. Secara teori usia dapat mempengaruhi terjadinya
katarak. Peningkatan usia menyebabkan perubahan dalam fungsi sel, struktur, jaringan, serta sistem
organ.12
Semakin bertambah usia seseorang proses non enzimatik terjadi pada protein lensa,
kerentanan terhadap proses oksidasi juga meningkat seiring dengan perkembangan genetik,
terjadinya perubahan susunan molekul lensa dan meningkatnya penghamburan cahaya. Risiko
kerusakan oksidatif akan meningkat pada usia 40 tahun disebabkan lensa manusia yang terus
bertumbuh dan mempengaruhi inti lensa dalam jangka waktu yang lama. Ini mengakibatkan inti
lensa menjadi lebih kaku dan transparansi lensa berkurang sehingga mengalami kesulitan dalam
kemampuan akomodasi mata dan memperberat dalam pembentukan katarak.13 Semakin tua usia
seseorang maka semakin besar kemungkinannya untuk terkena katarak. Ukuran lensa akan
bertambah dengan timbulnya serat-serat lensa baru seiring dengan meningkatnya usia, sehingga
kebeningan lensa berkurang.14
Jenis Kelamin
Hasil penelitian didapatkan bahwa yang mengalami kejadian katarak lebih banyak pada
perempuan (5%) daripada laki-laki (4,1%). Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa jenis
kelamin adalah salah satu faktor terjadinya katarak dengan PR= 1,141, 95% CI = 1,002-1,533 yang
berarti bahwa perempuan 1,141 kali lebih berisiko mengalami katarak dibandingan laki-laki setelah
dikontrol oleh variabel glaucoma, usia, riwayat diabetes, riwayat hipertensi, pendidikan, dan tipe
daerah. Secara teori perempuan lebih berisiko terkena katarak karena hormon ovarian
meningkatkan katarak yang didinduksi radiasi. Endogen utama estrogen, ẞ-estradiol memiliki
mitogenik dan efek anti-oksidatif pada konsentrasi fisiologis, sedangkan tingkat farmakologi
menginduksi stres oksidatif dan bertindak proapoptosis dalam lensa. Suplemen hormon percobaan
menunjukkan bahwa estrogen bertanggung jawab dalam pembentukan katarak. Tingkat hormon
dan konsentrasi metabolit yang berbeda akan menghasilkan kerentanan yang berbeda dalam
pembentukan katarak. Oleh karena itu, kadar hormon seks dapat dianggap sebagai faktor risiko
kataraktogenesis. Selain itu, albumin dan kadar trigliserida serum pada wanita dan defisiensi
estrogen pascamenopause dapat menjadi faktor yang terkait dengan kecenderungan yang lebih
besar untuk katarak.15
Pendidikan
Hasil penelitian didapatkan bahwa responden yang mengalami katarak mayoritas terjadi
pada responden yang pendidikan tinggi (5%) dibandingkan responden yang pendidikan rendah
(3,2%). Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa pendidikan merupakan faktor risiko dengan
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 256
nilai PR= 1,280, 95% CI= 1,070-1,533 yang berarti bahwa individu dengan pendidikan rendah
lebih berisiko terkena katarak 1,280 kali lebih besar dibandingkan individu dengan pendidikan
tinggi setelah dikontrol oleh variabel glaukoma, usia, riwayat diabetes, riwayat hipertensi, tipe
daerah, dan jenis kelamin. Pendidikan yang rendah pada masyarakat berdampak pada kurangnya
pemahaman dan kesadaran akan penyakit katarak, ditambah lagi dengan tenaga kesehatan yang
kurang dalam memberikan informasi atau penyuluhan tentang katarak. Umumnya masyarakat yang
memiliki pendidikan yang rendah belum memahami secara dini munculnya tanda-tanda penyakit
katarak.16
Salah satu indikator kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan, umumnya ini akan
terkait dengan penghasilan seseoarang. Penghasilan yang rendah akan mempengaruhi status nutrisi
seseorang. Pendidikan yang rendah umumnya akan menyebabkan seseorang memiliki pekerjaan
seperti nelayan, buruh dan pedagang jalanan yang kegiatan sehari-harinya terkena dengan sinar
matahari.17
Tipe Daerah
Hasil penelitian didapatkan bahwa responden yang mengalami katarak mayoritas bertempat
tinggal di kota (5%) dibandingkan responden yang tinggal di desa (4,1%). Hasil analisis statistik
multivariat menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tipe daerah dengan katarak
(PR = 0,847; 95% CI = 0,720-0,994) sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga yang tinggal
di perdesaan memiliki risiko 0,847 kali lebih rendah dibandingkan rumah tangga yang tinggal di
perkotaan setelah dikontrol oleh variabel glaucoma, usia, riwayat diabetes, riwayat hipertensi,
pendidikan, dan jenis kelamin. Secara teori tipe daerah bisa menyebabkan katarak karena
disebabkan oleh masyarakat pedesaan lebih banyak terpajan oleh sinar matahari karena mayoritas
masyarakat pedesaan umumnya bekerja sebagai petani, nelayan ataupun buruh. Pekerjaan ini dapat
dikategorikan sebagai pekerjaan di luar rumah sehingga ada pajanan kronis sinar matahari yang
diterima pekerja. Pekerjaan di luar rumah dan adanya pajanan radiasi ultraviolet (UV) B
merupakan faktor yang mempunyai hubungan dengan berkembangnya katarak. Paparan sinar UV
secara akut akan berdampak pada kulit, kornea dan lensa mata. Secara kronis, pajanan UV dengan
tingkat bermakna dan waktu yang berlebihan menyebabkan kulit kehilangan elastisitasnya atau
kulit mengalami penuaan dini dan beririsiko untuk terjadinya kanker kulit dan kekeruhan lensa.10
Peelitian Tana et.al juga memnyebutkan bahwa radiasi sinar ultraviolet dari sinar matahari yang
diperoleh secara terus menerus dapat mengakibatkan terjadinya kekeruhan pada lensa dan
menyebabkan katarak. 18
Tipe daerah menjadi faktor protektif kemungkinan dikarenakan jumlah
penduduk desa yang bekerja di lapangan seperti petani dan nelayan sudah banyak menurun. Badan
Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia yang bekerja di sektor pertanian
terus menurun dari 39,22 juta pada tahun 2013 menjadi 38,97 juta pada tahun 2014 dan jumlahnya
kembali turun menjadi 37,75 juta pada tahun 2015. Berkurangnya masyarakat yang bekerja sebagai
petani maka risiko terkena katarak akibat paparan sinar matahari saat bertani pun ikut menurun
sehingga tipe daerah menjadi faktor protektif.
Status Merokok
Hasil penelitian didapatkan bahwa responden yang mengalami katarak mayoritas terjadi
pada responden yang tidak merokok (4,7%) dibandingkan responden yang merokok (4,2%). Risiko
katarak enam kali lebih besar disebabkan karena merokok. Asap rokok merupakan sebagian kecil
dari berbagai jenis polutan dan sumber radikal bebas dalam tubuh. 19
Merokok dapat
mengakibatkan terjadinya penumpukan molekul berpigmen 3 hydroxikhynurine dan chromophores
sehingga menyebabkan terjadinya penguningan warna lensa.20
Merokok dapat menginduksi stress
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 257
oksidatif serta dihubungkan dengan penurunan kadar antioksidan, askorbat dan karotenoid yang
yang akan mempercepat kerusakan protein lensa bila terjadi secara terus menerus.21
Selain itu,
tembakau mengandung logam berat seperti timbal, kadmium, dan tembaga yang menumpuk dalam
lensa menyebabkan kerusakan secara langsung.22
Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara merokok dengan kejadian
katarak. Tidak adanya hubungan yang signifinan antara perilaku merokok dengan kejadian katarak
dicurigai karena karakteristik responden yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak
dibandingkan yang berjenis kelamin laki-laki. Selain itu, tidak berhubungannya merokok dengan
katarak kemungkinan karena ada nya perokok yang telah berhenti merokok sehingga mengurangi
risiko katarak. Terdapat 1098 responden yang telah berhenti merokok atau sebanyak 19,3 dari
keseluruhan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan di Swedia yang menyebutkan bahwa
terdapat penurunan risiko katarak pada seorang pria yang telah berhenti merokok. Karbon
monoksida yang dilepaskan saat pembakaran tembakau dan dihirup sebagai bagian asap rokok
dapat menjadi racun bagi tubuh pada tingkat tinggi. Karbon monoksida dapat terikat baik dengan
sel darah, kandungan tinggi dari zat ini mencegah sel darah mengikat oksigen. Setelah berhenti
merokok, kadar karbon monoksida di dalam tubuh akan menurun sampai pada tingkat normal dan
kadar oksigen di dalam darah kembali ke tingkat normal. Merokok dapat membuat mata memerah,
kering dan tampak lebih keruh. Apabila berhenti merokok maka efek-efek buruk pada mata ini
akan menghilang.
Riwayat Diabetes
Hasil penelitian didapatkan bahwa responden yang mengalami katarak mayoritas terjadi
pada responden yang penderita diabetes (11,5%) dibandingkan responden yang bukan penderita
diabetes (4,2%). Uji statistik menunjukkan terdapat hubungan antara diabetes dengan kejadian
katarak dengan PR = 1,882, 95% CI = 1,563-2,265 yang berarti bahwa penderita diabetes lebih
berisiko 1,5 kali lebih besar mengalami katarak dibandingkan yang bukan penderita diabetes
setelah dikontrol oleh variabel glaucoma, usia, riwayat hipertensi, pendidikan, tipe daerah, dan
jenis kelamin. Peningkatan kadar glukosa di dalam darah berperan penting dalam perkembangan
katarak. Hiperglikemia menyebabkan efek patologi yang dapat terlihat jelas pada jaringan tubuh
yang tidak bergantung langsung pada insulin pada saat selnya dimasuki oleh glukosa, seperti pada
lensa mata dan ginjal,sehingga ketika terjadi peningkatan konsentrasi gula di ekstraseluler, jaringan
ini tidak mampu mengatur transportasi glukosa yang masuk ke dalam sel. Beberapa penelitian
menunjukkan pada penderita diabetes jalur poliol memainkan peran dalam perkembangan katarak.
Di dalam lensa, melalui jalur poliol enzim aldose reduktase (AR) mengkatalisis reduksi glukosa
menjadi sorbitol. Sorbitol intrasel yang terakumulasi mengakibatkan perubahan osmotik sehingga
serat lensa hidropik mengalami degenerasi dan menghasilkan gula katarak. Enzim sorbitol
dehydrogenase (SD) di dalam lensa memproduksi sorbitol lebih cepat daripada diubah menjadi
fruktosa, dan terjadi peningkatan akumulasi sorbitol disebabkan sifat sorbitol yang sukar keluar
dari lensa melalui proses difusi. Hal ini menyebabkan infuse osmotik sebagai efek hiperosmotik
yang tercipta, guna menyeimbangkan gradien osmotik. Akibatnya, terjadi keruntuhan dan
pencairan serat lensa yang pada akhirnya membentuk kekeruhan lensa. Selain itu, pengembangan
ke arah katarak terjadi karena stres osmotik pada lensa akibat akumulasi sorbitol menginduksi
apoptosis pada sel epitel lensa. 23
Riwayat Hipertensi
Hasil penelitian didapatkan bahwa responden yang mengalami katarak mayoritas terjadi
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 258
pada responden yang penderita hipertensi (7,3%) dibandingkan responden yang bukan penderita
hipertensi (3,8%). Uji statistik menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara hipertensi
dengan kejadian katarak dengan PR = 1,505, 95% CI = 1,325-1,709 yang berarti bahwa penderita
hipertensi lebih berisiko 1,5 kali lebih besar mengalami katarak dibandingkan bukan penderita
hipertensi setelah dikontrol oleh variabel glaukoma, usia, riwayat diabetes, pendidikan, tipe daerah,
dan jenis kelamin. Pada saat tekanan darah seseorang meningkat, terdeteksi adanya peningkatan
protein C-reaktif (CRP). Hipertensi juga menyebabkan peningkatan sitokinin inflamasi seperti
interleukin-6 (IL-6), tumor necrosis factor-alpha (TNF-α). Beberapa referensi menyebutkan katarak
berhubungan erat dengan inflamasi sistemik yang hebat, karena perkembangan katarak melibatkan
hipertensi dalam jalur patologis melalui mekanisme inflamasi. Selain itu, mekanisme hipertensi
menyebabkan katarak senilis dengan cara mempengaruhi perubahan struktur protein lensa
menyebabkan ketidakseimbangan osmotik dalam lensa yang mengakibatkan terjadinya katarak
senilis.4
Riwayat Glaukoma
Hasil penelitian didapatkan bahwa responden yang mengalami katarak mayoritas terjadi
pada responden yang penderita glaukoma (40,8%) dibandingkan responden yang bukan penderita
glaukoma (4,3%). Hasil analisis multivariat menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara
glaukoma dengan katarak (PR = 11,276; 95% CI = 8,150-15,600) sehingga dapat disimpulkan
bahwa penderita glaukoma lebih berisiko terkena katarak 11,276 kali lebih besar dibandingkan
bukan penderita glaukoma setelah dikontrol oleh variabel usia, riwayat diabetes, riwayat hipertensi,
pendidikan, tipe daerah, dan jenis kelamin.
Secara teori hal ini bisa terjadi karena kaitan antara glaukoma dan katarak mungkin
berhubungan dengan tingkat keparahan glaukoma atau trauma operasi yang dilakukan untuk
meringankan glaukoma. Apabila glaukoma sudah berada pada tahap yang parah maka perlu
dilakukan adanya operasi. Setelah operasi maka akan menyebabkan traumatik kepada mata dan
meningkatkan risiko terjadinya katarak. Sehubungan dengan pengobatan glukoma, penderita
glaukoma mempunyai masalah dimana harus mengkonsumsi obat-obatan setiap hari sedangkan
paparan kumulatif dari obat glaukoma dapat meningkatkan risiko katarak. Semakin sering
penggunaan obat glaukoma maka semakin bertambah risiko terjadinya katarak. Obat seperti
kortikosteroid, statin, agen topikal biasanya digunakan dalam pengobatan glukoma.4 Obat
kortikosteroid dapat mempercepat terbentuknya katarak, hal ini dikarenakan adanya migrasi
abnormal dari sel epitel lensa. Aktivasi reseptor glukokortikoid pada sel epitel lensa mengakibatkan
terjadinya penurunan apotosis, proliferasi sel, dan menghambat diferensiasi sel. Berdasarkan
penjelasan diatas maka glaukoma dapat meningkatkan risiko katarak melalui operasi dan
pengobatannya.
Efek samping yang sering ditemukan pada pemakaian kortikosteroid pada pengobatan
glaukoma jangka panjang adalah adanya oksidasi protein struktural sebagai akibat terbentuknya
ikatan kovalen antara steroid dan protein lensa. Pembentukan ikatan kovalen antara kortikosteroid
dengan residu lisin pada lensa dan menurunnya kadar antioksidan asam askorbat dalam cairan
aqueous merupakan patofisiologi Protein Subcapsular Cataract (PSC) yang diakibatkan
kortikosteroid. Ikatan kovalen tersebut menyebabkan kekeruhan lensa pada katarak. Selain itu,
kortikosteroid menyebabkan akumulasi cairan dan koagulasi protein lensa yang menyebabkan
kekeruhan lensa sebagai dampak terhambatnya pompa Na-K pada lensa. 1
Glaukoma sering terjadi
pada usia diatas 50 tahun yaitu sekitar 55-65 tahun.24
Prevalensi galukoma umumnya lebih banyak
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 259
pada perempuan. Hal ini kemungkinan disebabkan sudut bilik mata depan perempuan volumenya
10% lebih kecil dibandingkan laki-laki.25
KESIMPULAN DAN SARAN
Adapun kesimpulan dari penelitian ini antara lain:
1. Hasil analisis univariat responden menunjukkan bahwa terdapat 4,6% responden yang
mengalami katarak di Indonesia pada tahun 2014 berdasarkan analisis data sekunder IFLS.
Jumlah responden berada pada usia >50 tahun (53,6%), jenis kelamin perempuan (52,8%),
pendidikan rendah (73,6%), merokok (36,9%), tinggal di desa (48,2 %), diabetes (4,7 %),
hipertensi (21,7 %), dan glaukoma (0,8%).
2. Hasil analisis bivariat didapatkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik
antara usia, jenis kelamin, pendidikan, tipe daerah, riwayat diabetes, riwayat hipertensi dan
glaukoma dengan katarak di Indonesia. Sedangkan variabel yang tidak berhubungan dengan
katarak yaitu status merokok.
3. Hasil analisis multivariat didapatkan bahwa variabel yang paling dominan berpengaruh
terhadap katarak yaitu glaukoma setelah dikontrol oleh variabel usia, jenis kelamin,
pendidikan, tipe daerah, riwayat diabetes dan riwayat hipertensi.
Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penggunaan alat pelindung diri agar terhindar dari sinar matahari bagi yang bekerja di luar
gedung.
2. Mengurangi penggunaan obat tetes mata karena dapat meningkatkan risiko katarak.
3. Melakukan pemeriksaan kesehatan mata secara rutin terutama bagi yang berusia diatas 40
tahun.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel independen lainnya seperti konsumsi
alkohol, riwayat keluarga dan pekerjaan.
DAFTAR PUSTAKA
1. Ilyas S, Sri RY. Ilmu Penyakit Mata Edisi Kelima. Jakarta: Balai Penerbit FK-UI; 2015. p.
210.
2. Mo‘otapu A, Rompas S, Bawotong, J. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian
Penyakit Katarak di Poli Mata RSUP Prof. Dr. R.D Kandou Manado. e-Journal Keperawatan
(eKp). 2015;3: 1–6.
3. Lukas VR, Pangkerego SB, Rumende RR. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Katarak
Senilis di Wilayah Kerja Puskesmas Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. E-
Jurnal Sariputra. 2017;4(2): 82–87.
4. Aini N A, Santik YDP. Kejadian Katarak Senilis di RSUD Tugurejo. Higea Journal of Public
Health. 2018;2(2).
5. Awopi G, Wahyuni TD. Sulasmini. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian
Katarak di Poliklinik Mata Puskesmas Dau Kabupaten Malang. Nursing News. 2016;1: 550–
556.
6. World Health Organization. Global Invititive For The Elimination Of Advoidable Blindness.
Geneva: WHO; 2013.
7. Bradford CA, Charnblee DR, Hunnewell JM, Morgan RK, Sigler SC. Basic Ophthalmology
for Medical Students and Primary Care Residents. 7th ed. San Francisco: American
Academy of Ophthalmology; 1999.
8. Kemenkes RI. Infodatin: Situasi Gangguan Penglihatan dan Kebutaan. Jakarta: Kementerian
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 260
Kesehatan Republik Indonesia; 2014.
9. Soehardjo. Faktor-Faktor Risiko, Penanganan Klinis dan Pengendalian. Jurnal: Kebutaan
Katarak. 2004;3.
10. Tana L, Rif‘ati L, Kristanto AY. Determinan Kejadian Katarak di Indonesia Riset Kesehatan
Dasar 2007. Buletin Penelitian Kesehatan. 2007;37: 114–125
11. Kemenkes RI. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013. Jakarta: Kementrian
Kesehatan Republik Indonesia; 2013.
12. Fatma. Pengantar Lanjut Usia. Jakarta: Rineka Cipta; 2010.
13. Michael R, Bron AJ. The Ageing Lens and Cataract: a Model of Normal and Pathological
Ageing. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences.
2011;366(1568): 1278–1292.
14. Pujiyanto. Faktor-Faktor Risiko yang Berpengaruh Terhadap Kejadian Katarak Senilis.
Semarang: Universitas Diponegoro; 2004.
15. Srinivasian S, Raman R, Swaminathan G. Incidence, Progession and Risk Factors For
Cataract in Type 2 Diabetes. Arvo Journals. 2017;58(13).
16. Hadini MA, Eso A. Wicaksono S. Analisis Faktor Risiko yang Berhubungan dengan
Kejadian Katarak Senilis Di RSU Bahteramas Tahun 2016. 2016; 256–267.
17. Laila A, Raupong I, Saimin J. Analisis Faktor-Faktor Risiko Kejadian Katarak di Daerah
Pesisir Kendari. 2017;4: 377–387.
18. Tana L, Delima, Enny H, Gondhowiharjo T. Katarak pada Petani dan Keluarganya di
Kecamatan Teluk Jambe Barat. Media Litbang Kesehatan. 2006;14(4).
19. Kartikasari IAKP, Nursayanto H, Yoga IBKW. Pola Konsumsi Makanan Sumber Beta-
Karoten dan Tingkat Konsumsi Vitamin Antioksidan pada Penderita dan Bukan Penderita
Katarak Senilis di Rumah Sakit Indera Provinsi Bali. Jurnal Virgin. 2015;1(1).
20. Yunianingsih A, Sahrudin, Ibrahim K. Analisis Faktor Risiko Kebiasaan Merokok, Paparan
Sinar Ultravioler dan Konsumsi Antioksidan Terhadap Kejadian Katarak di Poli Rumah
Umum Bahteramas Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017. Jurnal Ilmu
Mahasiswa Kesehatan Masyarakat. 2017;2(6).
21. Hamidi MNS, Royadi A. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Terjadinya Katarak
Senilis pada Pasien di Poli Mata RSUD Bangkinang. Jurnal Ners Universitas Pahlawan
Tuanku Tambusai. 2017;3(1).
22. Ye J, He J, Wang C, Wu H. Smoking and Risk of Age-Related Cataract: A Meta Analysis.
IOVS. 2012:53(7): 3885-3895.
23. Pollreisz A, Erfurth US. Diabetic Cataract-Pathogenesis, Epidemiology and Treatment.
Hindawi Publishing Corporation Journal of Ophthalmology. 2010;2010.
24. Ismandari F. Kebutaan pada Pasien Glaukoma Primer di Rumah Sakit Umum Dr Cipto
Mangunkusumo Jakarta. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional. 2011: 5(4).
25. Stamper RL, Lieberman MF, Drake MV. Becker-Shaffer‘s Diagnosis and Therapy of the
Glaucomas 8th ed., Elsevier: 2009.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 261
ANALISIS KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT TERHADAP
KEBAKARAN DI KELURAHAN TUAN KENTANG KECAMATAN
JAKABARING PALEMBANG 2019
Ade Pratama1, Novrikasari
2*
1Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya
2Bagian K3KL Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya
Jl. Palembang Prabumulih KM. 32, Indralaya Indah Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan
Corresponding email: [email protected]
ANALYSIS OF COMMUNITY PREPAREDNESS FOR FIRES IN TUAN
KENTANG VILLAGE IN JAKABARING DISTRICT PALEMBANG 2019
ABSTRACT
Fire is an emergency disaster and needs to be handled quickly, efficiently and appropriately to prevent
major losses. Preparedness is an activity carried out before a disaster occurs. The purpose of preparedness
is to minimize the impact or side effects of an event occurring in the community through effective, timely,
adequate, and efficient precautions and countermeasures. This research aims to look at the preparedness of
the community in the face of fires in Tuan Kentang Village, Jakabaring District Palembang 2019. This
research is quantitative research with a cross sectional approach, research instruments in the form of
questionnaires. The sample count is 104 KOs. Data analysis is done univariate and bivariate with the test
used is fisher exact test. The results showed that the variables associated with fire preparedness are
emergency response plan (p-value = 0.000), disaster warning system (p-value = 0.021, resource
mobilization (p-value =0.000), gender (p-value = 0.000), age (p-value = 0.012), education (p-value=0.023),
and house type (p-value=0.009), while unrelated knowledge variables (p-value = 0, 206), Attitude (p-value
= 0.119), and length of stay (p-value = 0.351). It can be concluded that there is a meaningful relationship
between emergency response plan, disaster warning system, resource mobilization, gender, age, education,
and type of house with fire preparedness in the community in Tuan Kentang Village, Jakabaring District
Palembang, so it is advisable to the relevant agencies to conduct regular socialization regarding fires and
training on emergency response plans as well as fire preparedness as an effort to understand and prepare
for the threat of fire hazards.
Keywords: fire, preparedness, preparedness parameters, individual characteristics
ABSTRAK
Kebakaran merupakan bencana yang bersifat darurat dan perlu penanganan yang cepat, efisien dan tepat
untuk mencegah timbulnya kerugian yang besar. Kesiapsiagaan merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum
kejadian bencana terjadi. Adapun yang menjadi tujuan dari kesiapsiagaan adalah untuk meminimalkan
dampak atau efek samping dari suatu kejadian yang terjadi dimasyarakat melalui tindakan pencegahan dan
penanggulangan yang efektif, tepat waktu, memadai, dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk melihat
kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kebakaran di Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Jakabaring
Palembang 2019. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional, Instrumen
penelitian berupa kuesioner . Jumlah sampel adalah 104 KK. Analisis data dilakukan secara univariat dan
bivariat dengan uji yang digunakan adalah uji Fisher Exact. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel
yang berhubungan dengan kesiapsiagaan kebakaran adalah rencana tanggap darurat (p-value = 0,000), sistem
peringatan bencana (p-value = 0,021, mobilisasi sumberdaya (p-value =0,000), jenis kelamin (p-value =
0,000), usia (p-value = 0,012), pendidikan (p-value= 0,023), dan jenis rumah (p-value= 0,009), sedangkan
yang tidak berhubungan yaitu variabel pengetahuan (p-value = 0, 206), Sikap (p- value = 0,119), dan lama
tinggal (p-value = 0,351). Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan bermakna antara rencana tanggap
darurat, sistem peringatan bencana, mobilisasi sumberdaya, jenis kelamin, usia, pendidikan, dan jenis rumah
dengan kesiapsiagaan kebakaran pada masyarakat di Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Jakabaring
Palembang, sehingga disarankan kepada instansi terkait untuk mengadakan sosialisasi berkala mengenai
kebakaran dan pelatihan mengenai rencana tanggap darurat maupun kesiapsiagaan kebakaran sebagai upaya
pemahaman dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bahaya kebakaran.
Kata kunci: kebakaran, kesiapsiagaan, parameter kesiapsiagaan, karakteristik individu
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 262
PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara yang masih berada dalam taraf berkembang, dengan
kondisi seperti itu sering membuat indonesia menjadi lemah dalam menghadapi suatu bencana,
baik itu bencana yang disebabkan oleh faktor alam atau bencana akibat kelalaian manusia.
Kebakaran pemukiman adalah bencana yang paling banyak kaitannya yang disebabkan oleh
kelalaian manusia.¹ Berdasarkan data dari International Association of Fire and Rescue Services
tahun 2017, menyatakan bahwa dari 31 negara yang mewakili 14% dari populasi dunia, terdapat 41,9
juta kali panggilan mengenai kebakaran, 3,5 juta kali kejadian kebakaran, 18.500 kematian warga
sipil akibat kebakaran dan 45.000 warga sipil yang mengalami luka-luka.² Selain itu, kebakaran
juga merupakan bencana yang bersifat darurat dan perlu penanganan yang cepat, efisien dan tepat
untuk mencegah timbulnya kerugian yang besar. Kerugian akibat kebakaran secara global di dunia
mencapai sekitar 10 miliar USD dan secara kasar diperkirakan sebesar 1% dari GDP (Gross
Domestic Product) Global per tahun dengan kerugian jiwa sebanyak 0,5 sampai 1,5 orang per
100.000 populasi di dunia per tahun.ᶟ Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) tercatat ada 1336 kasus kebakaran permukiman yang terjadi di Indonesia dari
tahun 2011-2018.⁴ Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran Penanggulangan Bencana Kota
Palembang Menunjukan bahwa sepanjang tahun 2018 telah terjadi kasus kebakaran sebanyak 260
kasus dengan 65 kasus kebakaran rumah yang terjadi dan tersebar dibeberapa wilayah dikota
Palembang, yang salah satunya adalah terjadi di Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Jakabaring
Palembang .
Kelurahan Tuan Kentang merupakan sentra industri salah satu kain khas Palembang yaitu
kain jumputan. Sebagai sentra industri kain jumputan khas palembang yang menjadikan kelurahan
Tuan Kentang yang harus dijaga dari berbagai resiko yang salah satunya adalah resiko kebakaran
pemukiman, mengingat karakteristik lokasi kelurahan tuan kentang juga merupakan lokasi
pemukiman yang padat serta lingkungan fisik yang berupa jalan dan gang yang sempit yang sulit
untuk dilalui mobil pemadam kebakaran jika terjadi suatu kejadian kebakaran, dimana waktu
efektif untuk pemadaman api sebelum api membesar adalah 3-10 menit.⁵
Kesiapsiagaan merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum kejadian bencana terjadi.
Adapun yang menjadi tujuan dari kesiapsiagaan adalah untuk meminimalkan dampak atau efek
samping dari suatu kejadian yang terjadi dimasyarakat melalui tindakan pencegahan dan
penanggulangan yang efektif, tepat waktu, memadai, dan efisien.⁶ Kesiapsiagaan juga berfungsi
untuk meminimalkan terhadap korban jiwa maupun korban harta benda ketika bencana terjadi.⁶
Kesiapsiagaan dalam menghadapi kejadian kebakaran sangat diperlukan untuk mengantisipasi
dampak buruk yang ditimbulkan dari kejadian kebakaran. Maka dari itu dilakukan penelitian terkait
Analisis Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Kebakaran Di Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan
Jakabaring Palembang‖
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif dengan desain cross sectional.
Sampel pada penelitian ini yaitu 104 KK (Kepala Keluarga) dimana teknik pengambilan sampel
dilakukan dengan purposive sampling dengan menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi. Analisis
data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis univariat dan bivariat dengan menggunakan
uji fisher exact dan Instrumen pada penelitian ini adalah kuesioner.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 263
HASIL PENELITIAN
Analisis Univariat
Penelitian ini dilakukan pada 104 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Tuan Kentang
Kecamatan Jakabaring Palembang, Mayoritas subjek penelitian berumur ≥ 30 tahun yaitu 68,8%,
dengan jenis kelamin subjek penelitian mayoritas perempuan yaitu 68,3% dan Hasil dari analisis
univariat penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Parameter Kesiapsiagaan dan Karakteristik
Individu
Parameter Kesiapsiagaan Frekuensi
(104)
Persentase
(100%)
Pengetahuan 1. Kurang baik
2. Baik
13
91
12,5 %
87,5 %
Sikap 1. Kurang baik
2. Baik
16
88
15,4 %
84,6 %
Rencana Tanggap Darurat
1. Kurang Baik 2. Baik
76 28
73,21 % 26,9 %
Sistem Peringatan Bencana
1. Kurang baik
2. Baik
81
23
77,9 %
22,1 %
Mobilisasi Sumberdaya
1. Kurang baik
2. Baik
93
11
89,4%
10,6%
Variabel Karakteristik Individu Frekuensi
(104)
Persentase
(100%)
Jenis Kelamin 1. Laki-Laki
2. Perempuan
33
71
31,7 %
68,3 %
Usia
1. Tua 2. Muda
83 21
79,8 % 20,2 %
Pendidikan
1. Pendidikan rendah
2. Pendidikan tinggi
50
50
50,0 %
50,0 % Lama Tinggal
1. < 5 Tahun
2. ≥ 5 Tahun
9
95
8,7 %
91,3 %
Jenis Rumah 1. Semi Permanen
2. Permanen
67
37
64,4 %
35,6 %
Berdasarkan tabel 1 diatas distribusi frekuensi responden berdasarkan parameter
kesiapsiagaan menunjukkan bahwa responden penelitian cenderung memiliki pengetahuan baik
yaitu 87,5% dibandingkan dengan pengetahuan kurang baik yaitu 12,5% kemudian untuk
parameter sikap hasil menunjukkan bahwa responden penelitian cenderung memiliki sikap baik
yaitu 84,6% dibandingkan dengan responden yang memiliki sikap kurang baik yaitu 15,4%.
Distribusi frekuensi rencana tanggap darurat 73,1% responden penelitian memiliki rencana tanggap
darurat yang kurang baik dan rencana tanggap darurat baik yaitu 26,9% Kemudian sistem
peringatan bencana yang kurang baik yaitu 77,9% dibandingkan dengan sistem peringatan bencana
yang baik yaitu 22,1%.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 264
Kemudian parameter mobilisasi sumber daya cenderung memiliki mobilisasi sumberdaya
yang kurang baik yaitu 89,4% dibandingkan dengan mobilisasi sumberdaya baik yaitu 10,6%.
Sedangkan distribusi frekuensi untuk jenis kelamin responden adalah mayoritas perempuan sebesar
68,3% dan laki-laki sebesar 31,7%. Distribusi frekuensi untuk usia responden mayoritas adalah
usia tua dimana kategori usia tua adalah ≥ 30 tahun sebanyak 79,8% dan sisanya usia muda yaitu
<30 tahun sebesar 20,2%.
Distribusi frekuensi untuk jenjang pendidikan terakhir responden adalah sama dimana
responden dengan pendidikan tinggi dan rendah yaitu sebesar 50,0%, distribusi frekuensi
responden berdasarkan lama tinggal ≥ 5 tahun yaitu sebesar 91,3% dan < 5 tahun yaitu sebesar 8,7
%. Kemudian distribusi frekuensi jenis rumah responden, mayoritas rumah responden adalah semi
permanen yaitu sebesar 64,4% dan sisanya adalah responden dengan jenis rumah permanen yaitu
sebesar 35,6% .
Analisis Bivariat
Hasil dari Analisis Bivariat pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan
bermakna secara statistik antara variabel pengetahuan, sikap, rencana tanggap darurat dan
pendidikan dengan kesiapsiagaan masyarakat terhadap kebakaran. Analisis Bivariat pada
penelitian ini dapat dilihat secara lengkap pada tabel berikut :
Tabel 2. Hasil Analisis Bivariat Untuk Setiap Variabel Penelitian
Variabel Penelitian p-value PR
(CI 95%)
Pengetahuan 0,206 1,197
(1,093-1,312)
Sikap 0,119 1,205
(1,097-1,325)
Rencana Tanggap Darurat 0,000 2,154
(1,447-3,206)
Sistem Peringatan Bencana 0,021 1,296
(0,979-1,714)
Mobilisasi Sumberdaya 0,000 5,145
(1,467-18,044)
Jenis Kelamin 0,000 0,624
(0,472-0,823)
Usia 0,012 1,355
(0,994-1,849)
Pendidikan 0,023 1,225
(1,040-1,442)
Lama tinggal 0,351 1,188
(1,008-1,296)
Jenis Rumah 0,009 1,268
(1,030-1,561)
PEMBAHASAN
Hubungan Pengetahuan dengan Kesiapsiagaan Kebakaran
Pada penelitian ini pengetahuan responden dibedakan menjadi dua kategori yaitu
pengetahuan responden dengan kategori kurang baik dan pengetahuan responden dengan kategori
baik di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa 87,5% responden penelitian memiliki
pengetahuan baik dan 12,5% responden memiliki pengetahuan kurang baik. Hasil penelitian juga
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 265
menunjukan bahwa 100% responden menyatakan bahwa kompor gas, korsleting listrik, rokok,
korek api serta cairan mudah terbakar adalah beberapa contoh yang dapat menjadi penyebab
kejadian kebakaran. Kemudian 93,3% responden penelitian menyatakan bahwa bentuk pencegahan
yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran adalah dengan mewaspadai rokok,
menjauhkan pemantik dan korek dari jangkauan anak-anak, penggunaan alat-alat listrik
secukupnya, serta perilaku memasak yang baik, perilaku masak yang baik dapat dicontohkan
seperti tidak meninggalkan kompor terlalu lama jika sedang memasak.
Berdasarkan hasil analisis data didapat p-value yaitu 0,206 atau p-value > 0,05 yang dapat
diartikan bahwa secara statistik tidak ada hubungan antara variabel pengetahuan dengan
kesiapsiagaan masyarakat terhadap kebakaran di Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Jakabaring
Palembang. Pengetahuan seseorang adalah tahu nya terhadap suatu objek setelah orang melakukan
penginderaan terhadap objek tersebut, dimana untuk terbentuknya suatu tindakan, domain
pentingnya adalah pengetahuan.⁷ Penelitian ini tidak berbanding lurus dengan Teori Lawrence
Green, dimana pada teori tersebut menjelaskan bahwa pengetahuan adalah faktor yang
mempermudah untuk terjadinya suatu perilaku pada seseorang.8 Penelitian ini sejalan dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Zahra Nurdina Fitriani pada bagian Spinning IV OE terkait faktor-
faktor yang berhubungan dengan kesiapsiagaan tanggap darurat di PT. APAC INTI CORPORA
SEMARANG.
Hubungan Sikap dengan Kesiapsiagaan Kebakaran
Pada penelitian ini sikap responden dibedakan menjadi dua yaitu sikap kurang baik dan
sikap baik berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa responden penelitian cenderung
memiliki sikap baik yaitu 84,6% dibandingkan dengan responden yang memiliki sikap kurang baik
yaitu 15,4%. Hasil penelitian menunjukan bahwa sikap responden yaitu 52,9% responden
penelitian setuju dan 44,2% sangat setuju bahwa kebakaran sering terjadi diakibatkan oleh
kelalaian manusia. Terkait sikap masyarakat dalam hal pencegahan mayoritas responden
menyatakan sangat setuju yaitu 55,8% dan 41,3% setuju untuk tidak membuang puntung rokok
sembarangan. Bentuk lain dari sikap masyarakat dalam hal pencegahan kebakaran adalah dengan
menggunakan peralatan listrik yang SNI (Standar Nasional Indonesia) dan mayoritas masyarakat
setuju dengan tindakan tersebut yaitu 62,5%.
Berdasarkan hasil analisis data penelitian diperoleh hasil p-value yaitu 0,119 atau p-value >
0,05 yang dapat diartikan bahwa tidak terdapat hubungan secara statistik antara variabel sikap
dengan variabel kesiapsiagaan pada penelitian ini. Sikap adalah respon seseoarang atau reaksi
seseorang yang masih tertutup terhadap suatu objek tertentu . sikap memiliki beberapa tingkatan
yaitu dari sikap yang menerima, merepon atau menanggapi, menghargai sampai pada sikap yang
bertanggung jawab.9
Penelitian ini berbanding lurus dengan penelitian yang dilakukan oleh Patuju
di Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan total responden yaitu 83 orang, yang
hasilnya adalah secara statistik variabel sikap tidak terdapat hubungan yang bermakna terhadap
kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran pemukiman.
Hubungan Rencana Tanggap Darurat dengan Kesiapsiagaan Kebakaran
Pada penelitian ini rencana tanggap darurat dibedakan menjadi dua kategori yaitu kurang
baik dan baik dan hasil menunjukkan bahwa 73,1% responden penelitian memiliki rencana tanggap
darurat yang kurang baik dan 26,9% responden penelitian memiliki rencana tanggap darurat yang
baik. Berdasarkan analisis data penelitian hasil p-value yaitu 0,000 atau p-value < 0,05 , yang
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 266
dapat diartikan bahwa secara statistik terdapat hubungan antara variabel rencana tanggap darurat
dengan kesiapsiagaan masyarakat terhadap kebakaran pada penelitian ini. Dari hasil penelitian
terkait rencana evakuasi untuk menyelamatkan diri ketika terjadi kebakaran mayoritas masyarakat
menjawab menghubungi pemadam kebakaran serta berusaha memadamkan api dengan peralatan
yang ada yakni 80,8% namun yang diharapkan peneliti adalah masyarakat menjawab menjauhi
lokasi kebakaran di karenakan hal ini terkait evakuasi untuk menyelamatkan diri. Ketersediaan
sarana jalur evakuasi bahwa 93,3% responden penelitian mengatakan bahwa daerah tempat tinggal
mereka tidak terdapat jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran, selanjutnya adalah terkait
ketersediaan kotak P3K, 88,5% tidak tersedia kotak P3K dirumah mereka.Hal ini tidak memenuhi
salah satu indikator yang ditetapkan LIPI (2006) terkait kesiapsiagaan bencana dalam parameter
rencana tanggap darurat yaitu tersedianya peta, tempat, jalur evakuasi keluarga, tempat
berkumpulnya keluarga dan tersedianya kotak P3K atau obat-obatan penting untuk pertolongan
pertama keluarga.6
selanjutnya adalah terkait pelatihan keadaan darurat dan manejemn bencana,
mayoritas masyarakat belum pernah mengikuti pelatihan keadaan darurat yakni 93,3% hal ini juga
tidak memenuhi indikator yang ditetapkan LIPI-UNESCO (2006) terkait kesiapsiagaan bencana
dalam parameter rencana tanggap darurat yaitu mengenai adanya anggota keluarga yang mengikuti
pelatihan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laila Fitriana di PT.
Sandang Asia Maju Abadi yang responden nya adalah karyawan bagian produksi, dimana hasilnya
adalah terdapat hubungan antara pelatihan dengan upaya kesiapsiagaan yang dilakukan oleh
karyawan bagian produksi untuk menghadapi ancaman bahaya kebakaran. sebagai contoh bentuk
antisipasi atau upaya dalam menghadapi kemungkinan kejadian kebakaran yang peristiwanya tidak
dapat di prediksi adalah dengan pelatihan terkait kebakaran.
Hubungan Sistem Peringatan Bencana dengan Kesiapsiagaan Kebakaran
Berdasarkan penelitian hasil p-value yaitu 0,021 (p-value < 0,05) yang artinya ada hubungan
antara variabel sistem peringatan bencana dengan kesiapsiagaan masyarakat terhadap kebakaran di
Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Jakabaring Palembang. Sistem peringatan bencana kebakaran
adalah serangkaian sistem yang berfungsi untuk memberitahukan akan terjadinya kejadian
kebakaran. Tujuan dari adanya sistem peringatan bencana kebakaran adalah di harapkan akan dapat
dikembangkan upaya-upaya yang tepat untuk mencegah atau paling tidak mengurangi terjadinya
dampak dari kejadian kebakaran bagi masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa di
Kelurahan Tuan Kentang belum terdapat sistem peringatan bencana kebakaran baik yang bersifat
tradisional maupun modern. Sistem peringatan bencana kebakaran merupakan sebuah sarana,
dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bahaya
kebakaran, dengan tersedianya suatu sistem peringatan kebakaran yang dapat memberikan alarm
informasi bagi masyarakat ketika terjadi kebakaran hal yang diharapkan adalah dapat mengurangi
dampak dari peristiwa kebakaran tersebut.
Hubungan Mobilisasi Sumberdaya dengan Kesiapsiagaan Kebakaran
Berdasarkan analisis data penelitian didapatkan hasil p-value yaitu 0,000 atau p-value <
0,05, yang dapat diartikan bahwa secara statistik terdapat hubungan antara variabel mobilisasi
sumberdaya dengan kesiapsiagaan masyarakat terhadap kebakaran. Hasil penelitian menunjukan
bahwa responden penelitian cenderung tidak menyediakan alokasi dana khusus untuk
kesiapsiagaan kejadian kebakaran yaitu 97,1% dan hanya 2,9% responden menyatakan
menyiapkan alokasi khusus seperti tabungan, investasi, maupun asuransi sebagai upaya
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 267
kesiapsiagaan terhadap kejadian kebakaran. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwasanya 96,2%
menyatakan ada keluarga yang bersedia membantu jika terjadi keadaan darurat kebakaran. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan LIPI-UNESCO/ISDR (2006) bahwasannya
dalam mengukur parameter mobilisasi sumberdaya adalah masyarakat bisa menjadi makhluk sosial
dalam membantu atau dibantu keluarga lain selama terjadinya bencana.6
Hubungan Jenis Kelamin dengan Kesiapsiagaan Kebakaran
Pada penelitian ini mayoritas responden berjenis kelamin perempuan dengan proporsi 70,6
% dan berjenis kelamin laki-laki 29,4%. Hasil analisis data penelitian didapatkan p-value yaitu
0,000 atau p-value < 0,05, yang dapat diartikan bahwa ada hubungan antara variabel jenis kelamin
dengan kesiapsiagaan masyarakat terhadap kebakaran. Peran, fungsi, serta tanggung jawab antara
laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil dari konstruksi sosial dan dapat berubah mengikuti
kesesuaian perkembangan jaman disebut jenis kelamin10
. Jenis kelamin juga dapat artikan interaksi
secara historis, sosial, budaya serta ikatan kontekstual11.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
tidak ada hubungan secara statistik antara variabel jenis kelamin dengan kesiapsiagaan masyarakat
terhadap kebakaran, dan dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin bisa mempengaruhi cara berpikir,
mempengaruhi perasaan dalam merasakan sesuatu, serta mempengaruhi cara bertindak yang semua
hal itu dapat berpengaruh pada kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran12
.
Hubungan Usia dengan Kesiapsiagaan dengan Kebakaran
Dalam penelitian ini variabel usia dibedakan menjadi dua yaitu usia tua dan usia muda usia
tua yaitu > 30 tahun dan usia muda yaitu < 30 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
sebagian besar responden penelitian tergolong ke dalam usia tua yaitu (79,8%) dan responden
penelitian yang tergolong dalam usia muda yaitu (20,2%). Berdasarkan analisis data penelitian
didapatkan hasil p-value yaitu 0,012 atau p-value < 0,05, yang dapat diartikan secara statistik
bahwa ada hubungan antara variabel usia dengan kesiapsiagaan masyarakat terhadap kebakaran.
Menurut teori Gibson usia merupakan faktor dari suatu individu, dimana artinya seiring
bertambahnya usia seseorang akan berpengaruh pada tingkat kedewasaan seseorang itu juga,
semakin bertambah dewasa seseorang akan mempengaruhi daya serap informasi seseorang tersebut
termasuk juga dalam hal ini terkait kesiapsiagaan13
.
Hubungan Pendidikan dengan Kesiapsiagaan Kebakaran
Dalam penelitian ini variabel pendidikan dibedakan menjadi pendidikan rendah yaitu SD-
SMP dan pendidikan tinggi yaitu SMA-PT. Hasil analisis data penelitian didapatkan hasil p-value
yaitu 0,012 atau p-value < 0,05, yang artinya secara statistik ada hubungan antara pendidikan
dengan kesiapsiagaan masyarakat terhadap kebakaran. Suatu usaha dalam mengembangkan
kepribadian serta kemampuan baik didalam maupun diluar sekolah dan berlangsung terus menerus
seumur hidup disebut pendidikan. Pendidikan berpengaruh pada proses belajar, yang artinya
seseorang dengan pendidikan yang tinggi akan lebih mudah menerima informasi baik dari orang
lain maupun dari edia massa. Semakin banyak informasi yang diterima akan berpengaruh pada
pengetahuan seseorang, pengetahuan memiliki kaitan erat dengan pendidikan, harapannya adalah
orang yang memiliki pendidikan tinggi akan memiliki pengetahuan yang luas pula14
.
Hubungan Lama Tinggal dengan Kesiapsiagaan Kebakaran
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 268
Pada penelitian ini lama tinggal dibedakan menjadi dua yaitu <5 tahun dan ≥ 5 tahun. Lama
tinggal dalam penelitian ini ditujukan pada responden yang telah tinggal dilokasi penelitian yaitu
kurang dari lima tahun dan lebih dari lima tahun, dengan asumsi bahwa responden yang lama
tinggalnya lebih dari lima tahun lebih memahami kondisi lingkungan disekitarnya dibandingkan
dengan responden yang lama tinggalnya kurang dari lima tahun. Namun jika lama tinggal nya saja
yang lama tetapi tidak diiringi dengan keikut sertaan pada kegiatan-kegiatan bersama dalam
masyarakat,serta minimnya pergaulan serta sosialisasi bersama dengan masyarakat lainnya, akan
berpengaruh pada kurangnya memahami kondisi lingkungan dan karakteristik tempat tinggal.
Berdasarkan hasil analisis data penelitian didapat hasil p-value yaitu 0,351 atau p-value >
0,05, yang secara statistik artinya tidak terdapat hubungan antara variabel lama tinggal dengan
kesiapsiagaan masyarakat terhadap kebakaran di Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Jakabaring
Palembang. Hal ini dikarenakan lama nya seseorang tinggal disuatu tempat atau suatu daerah bukan
faktor utama yang menentukan bahwa seseorang tersebut akan mengetahui informasi-informasi
terkait daerah atau tempat tersebut, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi diantaranya adalah
hubungan sosial masyarakat oang tersebut, mudah atau tidak orang tersebut beradaptasi, faktor lain
tersebut berdampak pada seberapa banyak informasi-informasi yang diperoleh orang tersebut,
dalam hal ini informasi terkait upaya-upaya kesiapsiagaan kebakaran.
Hubungan Jenis Rumah dengan Kesiapsiagaan Kebakaran
Pada penelitian ini jenis rumah dibedakan menjadi dua yaitu rumah semi permanen dan
rumah permanen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden cenderung memiliki jenis rumah
semi permanen yaitu 64,4% dan jenis rumah permanen yaitu 35,6%. Hasil analisis data penelitian
didapatkan hasil p-value yaitu 0,009 atau p-value < 0,05, yang artinya secara statistik ada
hubungan antara variabel jenis rumah dengan kesiapsiagaan masyarakat terhadap kebakaran.
Dalam penelitian ini rumah dengan kategori permanen adalah rumah yang sudah menggunakan
atap genteng, metal (metal roof), kemudian menggunakan kusen-kusen, daun pintu serta jendela
yang terbuat dari panel kayu dan ada juga yang sudah menggunakan panel kayu dengan kaca, lantai
rumah menggunakan keramik , menggunakan pondasi batu kali dan umumnya telah menggunakan
balok sloof, dan dinding rumah terbuat dari batu bata. Sedangkan untuk rumah dengan kategori
semi permanen adalah rumah yang mayoritas bahan yang digunakan adalah berbahan dasar kayu,
baik kusen, rangka jendela, dinding maupun lantai.15
Kayu merupakan benda padat yang mudah
terbakar dan kayu termasuk dalam klasifikasi kebakaran kelas A. Hal ini menunjukan adanya risiko
lebih tinggi yang dimiliki oleh responden yang memiliki rumah semi permanen untuk lebih
waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kejadian kebakaran.
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Distribusi frekuensi parameter kesiapsiagaan yaitu pengetahuan cenderung baik sebesar
87,5%, sikap cenderung baik sebesar 84,6%, Rencana tanggap darurat cenderung kurang
baik yaitu 73,1%, sistem peringatan bencana cenderung kurang baik yaitu 77,9%, dan
mobilisasi sumberdaya cenderung kurang baik yaitu 89,4%. Distribusi frekuensi
karakteristik responden yaitu jenis kelamin cenderung perempuan 68,3% , usia cenderung
usia tua 79,8, pendidikan cenderung sama yaitu 50% responden dengan pendidikan rendah
dan 50% responden dengan pendidikan tinggi, lama tinggal responden cenderung ≥ 5 tahun
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 269
91,3%, dan jenis rumah responden cenderung semi permanen 64,4%. Kemudian
kesiapsiagaan kebakaran masyarakat cenderung tidak siap yaitu 85,6%.
2. Hasil anilisis bivariat antara pengetahuan dan sikap, dengan kesiapsiagaan kebakaran tidak
memiliki hubungan yang bermakna, sedangkan untuk sistem peringatan bencana , rencana
tanggap darurat dan mobilisasi sumberdaya memiliki hubungan yang bermakna secara
statistik.
3. Hasil analisis bivariat antara jenis kelamin, usia, pendidikan, dan jenis rumah dengan
kesiapsiagaan kebakaran masyarakat terhadap kebakaran di Kelurahan Tuan Kentang
memiliki hubungan yang bermakna. Sedangkan variabel lama tinggal secara statistik tidak
menunjukan adanya hubungan yang bermakna.
Saran dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:
1. Perlu adanya sosiaslisasi berkala dari instansi resmi dalam penyampaian informasi
mengenai kebakaran baik pencegahan, penanggulangan maupun upaya kesiapsiagaan
kebakaran.
2. Perlu diadakan pelatihan/seminar/workshop kepada masyarakat mengenai rencana tanggap
darurat kebakaran
3. Bagi yang akan melakukan penelitan serupa mengenai kesiapsiagaan masyarakat terhadap
kebakaran, diharapkan agar bisa menambah variabel lain yang mendukung dalam
mengukur kesiapsiagaan kebakaran ( Seperti karakteristik lingkungan yaitu jarak rumah
dengan jalan raya mapun variabel-variabel lain seperti pelatihan manejemen bencana,
pengalaman menghadapi bencana, dan lain-lain) guna mendapatkan hasil yang lebih
absolut.
DAFTAR PUSTAKA
1. Wiranto, S. A. Modul Ajar Pengintegrasian Pengurangan Resiko Kebakaran: Bahan Ajar
Pengayaan Bagi Guru SMA/SMK/MA/MAK. Jakarta: Pusat Kurikulum Badan
Penelitian dan Badan Pengembangan Kementrian PendidikanNasional. 2009.
2. Brushlinsky, Ahrens, Sokolov, and Wagner. Center of Fire Statistic.Building & Plant
Institute dan Ditjen Binawas Depnaker RI.2005. Training Penanggulangan Kebakaran.
Jakarta. 2017;
3. Haryono, Nono, Adrianus Pangaribuan, and Fatma Lestari. ―Evaluasi Penerapan
Keselamatan Kebakaran Menggunakan Computerized Fire Safety Evaluation
System(CFSES) Pada Gedung Pendidikan Dan Laboratorium Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Indonesia Tahun 2014‖. 2014;
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Data Kejadian Bencana Kebakaran
Pemukiman.2018.
5. Ramli, Soehatman. Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran (Fire Management). Jakarta :
Dian Rakyat. 2010.
6. LIPI, UNESCO/ ISDR. Kajian Kesiapsiagaan masyarakat dalam Menghadapi Ancaman
Bencana Alam. Jakarta: LIPI Press. 2006.
7. Sudiastono B. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pengetahuan dan Sikap
Kesiapsiagaan Bencana pada Mahasiswa Keperawatan Universitas Muhammadiyah
Semarang.Fakultas Keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang. 2015;
8. Akbar IN. Beberapa Faktor yang Berhubungan dengan Praktik Keselamatan Kebakaran
Operator SPBU dalam Upaya Pencegahan Kebakaran di Areal SPBU Kecamatan Ngaliyan
Semarang Barat. Fakultas KesehataMasyarakat Universitas Diponegoro. 2008;
9. Soebiyono SW. Pengaruh Pelatihan Terhadap KeterampilanKaryawan dalam Penggunaan
APAR di Apartemen Mediterania Garden II Agung Podomoro Jakarta Barat. Fakultas Ilmu
Kesehatan Universitas Esa Unggul.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 270
10. BKKBN - Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan. Konsep dan Teori
Gender.Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 2007.
11. Alston, Margaret. 2013. Research, Action dan Policy: Addressing the Gendered Impacts of
Climate Change. Springer Science+Business Media Dordrecht. 2013; DOI 10.1007/978-
94-007-5518- 5.
12. Zahra Nurdina, F. et.al. 2019, ―Faktor-faktor yang berhubungan dengan kesiapsiagaan
tanggap darurat ‖PT. APAC INTI CORPORASEMARANG (Studi Pada Bagian Spinning
IV OE)‖, Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-journal) Universitas Diponegoro. 2019; Vol.7,
No.4. http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm.
13. Gibson, J.L, Ivancevich, J.M, Donnelly, J.H. Organisasi : Perilaku, Struktur dan Proses
(Terjemahan). Jakarta : Erlangga. 1987.
14. Notoatmodjo, Soekidjo. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Cetakan Kesatu, Jakarta :
Rineka Cipta. 2003.
15. Hadibroto, B.Analisis Karakteristik Rumah di Kota Medan Terhadap Pedoman Teknis
Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa. Jurnal Education Building. 2017; Vol.3,
No.2 https://jurnal.unimed.ac.id
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 271
DETEKSI RESIKO ANEMIA DAN PENDIDIKAN GIZI PRAKONSEPSI PADA
CALON PENGANTIN WANITA DI KABUPATEN OKI SUMATERA SELATAN
Ditia Fitri Arinda
1*, Rostika Flora
2, Widya Lionita
3
1,2 Bagian Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya
3Bagian Promosi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya
Jl. Palembang Prabumulih KM. 32, Indralaya Indah Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan
Corresponding email: [email protected]
ANEMIA RISK DETECTION AND PRECONCEPTION NUTRITION EDUCATION FOR
WOMEN PROSPECTIVE IN OKI DISTRICT, SOUTH SUMATRA
ABSTRAC
Stunting is a linear growth disorder characterized by height that is not suitable for age.Stunting causes
physical growth and intellectuality of toddlers to experience disruption which results in the quality of a
country's Human Resources. The percentage of stunting in South Sumatra Province in the toddler group was
22.8%.The percentage of stunting reflects the cumulative effect of malnutrition and infection early even
before birth. Failure to fulfill nutrition in 1000 HPK is largely beyond repair.The focus of stunting
interventions can be done since early pregnancy and even before pregnancy. Knowledge about stunting can
be intervention with integrated preconception nutrition education.Included in conveying nutritional
information, programs involving various components of government are needed to run the intervention
program consistently.The purpose of this study was to determine the effect of preconception nutrition
education on women of childbearing age as a preventive stunting event in OKI Regency, South Sumatra.This
study used a quasi-experimental pre-post one group design with purposive sampling technique and data
analysis using paired t-test. The results of this study obtained a mean pre-test 50.4857, while the mean post-
test 50.9714. The average change in knowledge of respondents after being given health education was
10.48571 with a standard deviation of 1.296668. The P-Value 0.111 (P>0,05) results, which means that the
provision of health education does not have a significant influence on the knowledge of respondents.There is
a difference in knowledge scores before and after the provision of preconception nutrition education which is
not significant. Nevertheless, extension services still make an effective contribution in increasing knowledge
of stunting information
Keywords: anemia, education, nutrition, preconception, women
ABSTRAK
Stunting merupakan gangguan pertumbuhan secara linier yang ditandai dengan ukuran tinggi badan yang
tidak sesuai dengan umur. Stunting menyebabkan pertumbuhan fisik dan intelektualitas balita mengalami
gangguan yang berakibat pada kualitas Sumber Daya Manusia suatu Negara. Stunting menggambarkan
dampak dari kurangnya asupan gizi dan kejadian infeksi sejak dini dalam waktu yang lama bahkan sebelum
bayi lahir. Kegagalan pemenuhan gizi pada 1000 HPK ini sebagian besar tidak bisa diperbaiki setelahnya.
Permasalahan stunting yang terjadi salah satunya disebabkan karena kurangnya pengetahuan gizi ibu
mengenai 1000 HPK. Fokus pemberian intervensi stunting dapat di lakukan bahkan sebelum kehamilan.
Pengetahuan mengenai stunting dapat diperbaiki dengan pendidikan gizi prakonsepsi secara terintegrasi dan
melibatkan multisektor sangat diperlukan guna berjalannya program intervensi secara konsisten. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh edukasi gizi prakonsepsi pada calon pengantin wanita sebagai
preventif kejadian stunting di Kabupaten OKI, Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan desain Quasi
eksperiment pre-post one group dengan purposive sampling dan analisis data menggunakan paired t-test.
Hasil penelitian ini menunjukkan sebelum mendapatkan pendidikan kesehatan tentang gizi prakonsepsi rata-
rata pengetahuan responden tentang gizi prakonsepsi adalah 50,4857, sedangkan rata-rata pengetahuan
responden tentang gizi prakonsepsi meningkat setelah dilakukan intervensi menjadi 50,9714. Rata-rata
pengetahuan responden setelah diberikan pendidikan gizi prakonsepsi adalah 10,48571dengan standar deviasi
1,29668. Hasil p-value 0,111 (p>0,05), menunjukkan bahwa pemberian pendidikan gizi prakonsepsi tidak
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan responden. Meskipun demikian, penyuluhanan
tetap memberikan kontribusi yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan pasangan usia subur terhadap
informasi mengenai stunting.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 272
Kata Kunci: anemia, pendidikan, gizi, prakonsepsi, wanita
PENDAHULUAN
Stunting merupakan gangguan pertumbuhan secara linier yang ditandai dengan ukuran tinggi
badan yang tidak sesuai dengan umur. Stunting dapat di lihat dari indikator skor-Z tinggi badan
menurut umur (TB/U) kurang dari -2 standar deviasi. Stunting mengindikasikan kejadian gizi salah
yang akumukatif dalam jangka waktu yang lama karena tidak adekuatnya konsumsi zat gizi makro
dan mikro, pola asuh yang tidak tepat dan kondisi kesehatan yang kurang baik 1,2
. Stunting menjadi
salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs) yakni poin kedua yang bertujuan untuk
menghilangkan kelaparan dan berbagai bentuk malnutrisi serta menjamin semua orang dapat
menikmati makanan yang aman dan bernutrisi pada tahun 2030. Joint Child Malnutrition
Eltimates (2018) menunjukkan bahwa 150,8 juta atau sama dengan sekitar 22% balita di dunia
mengalami stunting. Indonesia menjadi salah satu Negara dengan prevalensi stunting tertinggi ke-3
di South-East Asia Regional (SEAR). Prevalensi rata-rata balita stunting di Indonesia pads tahun
2005 sampai 2017 sebesar 36,4% 3,4
.
Data Riskesdas 2018 menunjukkan terjadinya grafik penurunan angka stunting di
bandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2013 proporsi stunting sebesar 37,2% dan pada
tahun 2018 turn menjadi 30,8% yang terdiri atas 19,3% balita pendek dan 11,5% balita sangat
pendek. Menurut data PSG 2017, persentase stunting pada kelompok balita secara nasional sebesar
29,6%. Persentase stunting di Provinsi Sumatera Selatan pada kelompok balita sebesar 22,8%. Di
Sumatera Selatan, beberapa kabupaten yang menjadi perhatian karena angka stunting yang tinggi
diantaranya adalah Musi Rawas Utara (32,8%), Banyuasin (32,8%), Ogan Ilir (29,5%), Lahat
(28,2%), Empat Lawang (27,7%), dan Ogan Komering Ilir (OKI) sebesar 22,6%. Masalah Stunting
di Indonesia akan dianggap cukup berat apabila 30-39% merupakan prevalensi pendek dan
dianggap serius apabila ≥40% prevalensi pendek. Stunting menggambarkan dampak dari
kurangnya asupan gizi dan kejadian infeksi sejak dini dalam waktu yang lama bahkan sebelum bayi
lahir 5,6
.
Penyebab Stunting bersifat kompleks dan multi faktor. Kondisi ekonomi, politik mendasari
status sosial ekonomi, pendidikan dan lingkungan yang berpengaruh terhadap higien sanitasi,
kejadian infeksi dan asupan makan yang tidak adekuat. Asupan gizi yang tidak memenuhi
kebutuhan balita akan berdampak terhadap kesehatan dan kecerdasan, sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya peningkatan angka morbiditas dan mortalitas pada balita, fungsi kognitif
dan psikologis pada masa sekolah menjadi rendah dan peningkatan biaya kesehatan6.
Program Intervensi Stunting dapat dilakukan saat prenatal dan pascanatal. Dalam lingkup
global pencegahan stunting dilakukan melalui strategi SUN(Scalling Up Nutrition), di Indonesia
dikenal dengan Program 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) melalui Gerakan Nasional
Sadar Gizi dalam Rangka Percepatan Perbaikan Gizi4. 1000 HPK adalah tahapan kehidupan
dimulai sejak terjadinya kosepsi dan terbentuknya janin di kandungan sampai anak berusia dua
tahun. 1000 HPK adalah masa golden age dan masa untuk memperbaiki (window of opportunity).
Kegagalan pemenuhan gizi pada 1000 HPK ini sebagian besar tidak bisa diperbaiki setelahnya.
Sasaran utama program 1000 HPK adalah anak dibawah usia dua tahun, remaja putri, ibu hamil,
dan ibu menyusui5.
Pasangan usia subur merupakan salah satu kelompok sasaran yang perlu diintervensi dalam
upaya mencegah angka stunting11. Pada pasangan usia subur yang baru menikah, memiliki anak
juga menjadi hal yang paling diharapkan. Prinsip dari pencegahan stunting adalah pentingnya
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 273
untuk menjaga status gizi dan kesehatan ibu sebelum dan selama kehamilan agar ibu terhidar dari
resiko malnutrisi yang dapat mengakibatkan kelahiran bayi pendek (<48 cm) dan BBLR (<2500
gram) yang memiliki risiko stunting. Sehingga perlu adanya upaya pencegahan dimulai dari
persiapan kehamilan yang akan berdampak pada kelahiran bayi, sehingga persiapan harus sedini
mungkin dengan tujuan supaya memiliki bayi yang sehat sempurna dengan status gizi yang baik.5,12
Selama ini Pasangan usia subur selama ini hanya berfokus pada kondisi kehamilan dan
kelahiran, banyak yang belum mengetahui bahwa titik kritis terjadi saat sebelum konsepsi. Hal
tersebut dapat diajadikan evaluasi bahwa masih minimnya informasi yang disampaikan kepada
masyarakat terkait pengetahuan tentang gizi prakonsepsi13
. Bayi yang normal dan sehat sangat
dipengaruhi dari status gizi ibu selama 6 bulan pertama masa prakonsepsi14
.
Kesehatan dan Status Gizi Ibu saat masa sebelum kehamilan, masa kehamilan dan menyusui
menjadi kunci pertumbuhan dan perkembagan anak yang akan dilahirkan. Sehingga menjadi
kewajiban seorang ibu untuk menjaga status gizinya, tentunya hal juga sangat perlu dukungan dari
suami dan keluarga besar. Ibu dengan status gizi yang buruk memiliki resiko 7 kali lebih besar
melahirkan anak yang stunting dibandingkan ibu dengan status gizi baik15
. Ibu hamil KEK beresiko
mengandung janin dengan pertumbuhan yang terhambat dan kelahiran bayi BBLR16
.
Lingkar lengan atas (LiLA) <23,5cm menjadi tanda bahwa KEK telah terjadi pada ibu hamil.
Ibu hamil dengan status gizi kurang berisiko 3 kali lebih besar dibandingkan ibu dengan status gizi
normal untuk menderita anemia, sehingga ibu harus mengonsumsi Tabtet Tambah Darah (TTD)
setiap hari selama kehamilan (minimal 90 tablet selama kehamilan)17,18
. Pemenuhan zat gizi
lainnya juga harus tetap diperhatikan dan juga didukung dengan sanitasi lingkungan yang terjamin
agar ibu terhindar dari masalah gizi serta terhindar dari resiko melahirkan anak yang stunting19.
Permasalahan stunting yang terjadi salah satunya disebabkan karena kurangnya pengetahuan
gizi ibu mengenai 1000 HPK. Pengetahuan gizi yang kurang akan mempengaruhi perilaku
terhadap pola asuh dan pola pemberian makan pada anak20
. Pengetahuan gizi selayaknya
didapatkan bukan hanya dari pendidikan formal saja, tetapi banyak informasi yang bisa didapatkan
dari pendidikan non-formal. Pengetahuan bisa didapatkan dari infromasi yang disampaikan orang
lain melalui berbagai media seperti televisi, radio, koran, hingga penyebaran informasi berdasarkan
pengalaman orang lain yang dibagikan melalui media sosial berbasis jaringan internet22
.
Pengetahuan dan sikap yang baik terhadap kesehatan dan gizi sangat dipengaruhi ada
tidaknya pendidikan kesehatan yang disampaikan dan disebarkan kepada masyarakat23
. Informasi
kesehatan sebenarnya telah banyak tersebar di masyarakat, namun untuk mendukung informasi
tersebut mudah dipahami dan mampu memberikan dampak terhadap perubahan pengetahuan dan
sikap masyarakat, diharapkan informasi yang disampaiakan didukung dengan media yang menarik
dan interaktif bagi masayarakat sehingga lebih mudah diingat. Sehingga tujuan akhir penyampaian
pendidikan tersebut dapat tercapai, yaitu mampu mengubah sikap dan perilaku masyarakat menjadi
lebih baik24
Fokus pemberian intervensi stunting dapat di lakukan sejak awal kehamilan dan bahkan saat
sebelum hamil. Banyak wanita tidak mendapatkan akses pengetahuan gizi saat lima sampai enam
bulan kehamilan8. Tumbuh kembang individu sudah dimulai sejak terbentuknya janin di dalam
kandungan ibu, sampai menjadi remaja hingga menjadi manusia dewasa9,12
. Pengetahuan mengenai
stunting dapat dilakukan dengan pendidikan gizi prakonsepsi secara terintegrasi. Termasuk dalam
menyampaikan informasi gizi, program yang melibatkan berbagai komponen pemerintahan sangat
diperlukan guna berjalannya program intervensi secara konsisten13
. Untuk mencapai tujuan
pendidikan kesehatan, informasi yang disampaikan harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan
karakteritik objek pendidikan sehingga mudah dipahami, media pendidikan pendidikan yang
sederhana dan sesuai dengan sasaran dari pendidikan yang dilakukan10,11,24
.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 274
METODE
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan SP Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI),
Sumatera Selatan. Waktu penelitian selama 1 tahun dengan waktu interveni pada bulan April – Juni
2019. Jenis penelitian eksperimen deskriptif analitik dengan Metode penelitian quasi eksperiment,
pre-post test one group.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wanita usia subur yang tercatat di Kantor
Urusan Agama ( KUA) di Kecamatan SP Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera
Selatan periode bulan April-Mei 2019 dengan jumlah sampel sebanyak 35 orang.
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling dengan
menggunkan kriteria inklusi menjadi responden adalah wanita usia produktif (15-49 tahun,
Kemenkes RI), dan bersedia mengikuti penelitian sampai selesai. Kriteria eksklusinya adalah
wanita yang sedang menjalani diit tertentu karena penyakit.
Data yang dianalisis adalah data univariat dan bivariat. Paired t-test digunakan pada
analisis bivariat untuk melihat perbedaan sebelum dan sesudah intervensi dengan signifikansi
p<0,05. Data yang dianalisis adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan
melalui kuesioner dan wawancara terhadap informan (indepth interview). Data sekunder
didapatkan berdasarkan data yang diperoleh dari puskesmas dan kantor KUA terdiri dari data profil
lembaga, dokumen terkait daftar pesert dan laporan tahunan.
HASIL PENELITIAN
Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian
Karakteristik n %
Usia <20
20-35
6
29
17,1
82,9
Pendidikan
Terakhir
SD
SMP
SMA
PT
1
4
27
3
2,9
11,4
77,1
8,6
Indeks Massa
Tubuh
Kekurangan BB tingkat berat
Kekurangan BB tingkat ringan
Normal
Kelebihan BB tingkat ringan Kelebihan BB tingkat berat
2
5
24
2 2
5,7
14,3
68,6
5,7 5,7
LILA Normal
Tidak Normal
29
6
82,9
17,1
Kadar HB Normal Tidak Normal
23 12
65,7 34,3
Berdasarkan hasil analisis table diatas, dari 35 responden dapat dilihat bahwa 29 orang
(82,9%) berada pada rentang umur 20-35 tahun. Mayoritas tingkat pendidikan responden SMA
yaitu 27 orang (77,1%). Mayoritas indeks massa tubuh responden berada dalam kondisi normal
sebanyak 24 orang (68,6%). Selanjutnya, mayoritas ukuran lingkar lengan atas responden berada
dalam kondisi normal sebanyak 29 orang (82,9%). Dan mayoritas kadar HB responden berada
dalam kondisi normal sebanyak 23 responden (65,7%).
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 275
Tabel 2. Hasil Analisis Pengetahuan Pretest dan Post Testtest
Tabel berikut menunjukkan bahwa sebelum mendapatkan pendidikan kesehatan tentang
gizi prakonsepsi rata-rata pengetahuan responden tentang gizi prakonsepsi adalah 5,4857 (SD
2,33101). Kemudian Rata-rata pengetahuan terkait gizi prakonsepsi meningkat setelah dilakukan
intervensi, yaitu menjadi 5,9714 (SD 1,94763). Pengetahuan responden setelah diberikan
pendidikan kesehatan rata-rata mengalami perubahan sebesar 0,48571 (SD 1,29668). Berdasarkan
Uji paired t-test didapatkan hasil p-value 0,111, yang berarti bahwa pendidikan kesehatan tidak
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan responden.
PEMBAHASAN
Hasil penelitian yang didapatkan mengenai pengetahuan pencegahan stunting sebelum
pendidikan menunjukkan skor rata-rata sebesar 5,4857. Sedangkan pada setelah diberikan
pendidikan prakonsepsi terjadi peningkatan pengetahuan yang menunjukkan skor rata-rata sebesar
5,9714.
Pengetahuan merupakan informasi, maupun ide yang didapatkan seseorang melalui
penyampaian media maupun secara langsung dari seseorang baik secara formal maupun informal25
.
Pengetahuan juga merupakan suatu proses pembentukan informasi dan pemahaman yang dilakukan
terus-menerus oleh seseorang dan masih akan terus mengalami perubahan baru. Dalam pemberian
pendidikan kesehatan mengenai stunting, responden yang pernah terpapar tentang materi stunting
atau 1000 HPK lebih melekat pada ingatannya yang pernah dialami. Sehingga saat diberikan
pendidikan kesehatan mengenai stunting akan lebih mudah menyerap materi yang diberikan.
Intelegensia seseorang dipengaruhi beberapa faktor yaitu pembawaan, pembentukan, minat dan
pembawaan yang khas serta kebebasan.26
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa media yang sesuai dengan sasaran, menarik dan
penyampaian juga dilakukan dengan strategi yang tepat dapat meningkatkan pengetahuan wanita
usia subur tentang upaya pencegahan stunting. Selain itu, hal ini juga dapat menjadi usaha untuk
meningkatkan sosialisasi pencegahan stunting di wilayah Sirah Pulau Padang. Penggunaan media
baik tulisan, gambar ataupun instrumen yang dapat didemokan mampu meningkatkan pengetahuan
lebih signifikan dibandingkan hanya dengan metode ceramah tanpa alat bantu. Media dirancang
agar penerimaan informasi dapat lebih maksimal27
.
Meskipun hasil uji beda menunjukkan p-value yang tidak signifikan, skor pengetahuan
menunjukkan peningkatan. Skor pengetahuan responden mengalami peningkatan dikarenakan
responden fokus pada apa yang disampaikan oleh pemberi materi, pemateri mengupayakan
informasi yang disampaikan dapat mudah dipahami dan dengan ilustrasi yang sederhana sehingga
responden dapat mengambil kesimpulan dan maksud dari informasi tersebut secara tepat. Ketika
dalam kelompok yang lebih kecil, fokus dan perhatian responden benar-benar akan tertuju pada
penceramah (peneliti) yang sedang menyampaikan materi. Hal ini sejalan dengan penelitian
Maelafitri yang menyatakan bahwa media pendidikan dengan buku bergambar 3D merupakan
sebuah media visual yang berpengaruh terhadap pengetahuan mengenai anemia pada remaja putri
dengan dengan nilai signifikan 0,0001<0,005. Pendidikan dengan ceramah yang didukung dengan
Pengetahuan Mean SD Mean SD P
Pretest 5,4857 2,33101 0,48571 1,29668 0,111
Posttest 5,9714 1,94763
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 276
gambar dan ilustrasi pada bahan informasi yang educator sampaikan, lebih efektif dibandingkan
multimedia flash card yang berisikn tulisan dan gambar. Metode ceramah tetap efektif karena
edukator mampu menjelakan dengan jelas dan bahasa yang mudah diterima oleh reponden, serta
mampu berdiskusi secqra interaktif dengan responden. Pengetahuan responden mengalami
peningkatan setelah diberikan intervensi berupa pendidikan gizi dengan metode ceramah
dibandingkan dengan sebelum diberikan intervensi (p<0,001)28
.
Menurut peneliti, peningkatan skor pengetahuan pada kelompok perlakuan tersebut mungkin
disebabkan karena berbagai faktor yang berkaitan dengan penerimaan informasi terkait stunting.
Diantaranya adalah, Konten materi yang disanpaikan berkaitan dengan hal yang sangat penting
untuk mereka yaitu tentang status gizi dan kesehatan anak. Seperti yang kita ketahui, wanita usia
subur cenderung masih memiliki anak yg usianya belia dan jika yang hendak menikah, sudah
terdaftar di KUA untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga hal ini menjadi hal yang cukup
menggerakkan mereka untuk lebih serius mendengarkan karna hal ini merupakan hal penting yang
sangat berkaitan dengan prioritas mereka saat ini. Selain itu media yang digunakan untuk
menyampaikan informasi sebelumnya kepada responden membuat responden cukup menerima
informasi, dapat juga disebabkan karena pemberi informasi (peneliti) adalah orang yang
diperkenalkan kepada responden sebagai seorang pakar dibidang gizi sehingga responden dengan
serius mendengarkan informasi yang disampaikan oleh orang yang memangmenurut mereka ahli
dibidangnya. Kesuksesan penyampaian informasi pada akhirnya akan ditentukan oleh mutu dan
kualitas seseorang yang menyampaikan informasi tersebut secara lugas dan meyakinkan sehingga
informasinya mudah diingat.29
Penelitian lainnya menyatakan bahwa penggunaan media visual yang unik dan menarik yang
belum pernah mereka lihat juga mampu meningkatkan pengetahuan pasangan calon pengantin
tentang informasi yang berkaitan dengan 1000 Hari Pertama Kehidupan. Metode yqng digunakan
adalah dengan memberikan kartu berisi informasi yang dapat dibaca berulang kali, serta bentuk
yang unik dari Kartu Cinta Anak (KCA) mampu memberikan peningkatan pengetahuan secara
signifikan.29,30
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa terdapat
perbedaan skor pengetahuan sebelum dan sesudah pemberian edukasi gizi prakonsepsi meskipun
tidak signifikan. Meskipun demikian, penyuluhanan tetap memberikan kontribusi yang efektif
dalam meningkatkan pengetahuan pasangan usia subur terhadap informasi mengenai stunting.
DAFTAR PUSTAKA
1. KDPDTT. Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting. Jakarta. 2017.
2. Apriluana, Gladys dan Fikawati, Sandra. Analisis Faktor-Faktor Risiko terhadap Kejadian
Stunting pada Balita (0-59 Bulan) di Negara Berkembang dan Asia Tenggara. Media
Litbangke. 2018; Volume 28 Nomor 4 Halaman 247 – 256.
3. Kemenkes. Kesehatan dalam Kerangka Sustainable Development Goals (SDGs). Jakarta. 2015.
4. United Nations Children‘s Fund, World Health Organization, World Bank Group. Levels and Trends in
Child Malnutrition: Key Findings of The 2018 Edition of The Joint Child Malnutrition Estimates. 2018.
5. Pusdatin Kemenkes RI,. Buletin Jendela Data dan Informasi : Situasi Balita Pendek (stunting)
di Indonesia. Jakarta. 2018.
6. Kemenkes. Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2017. Jakarta. 2018.
7. Maelafitri N, Laras S, Anugrah N., The Effect of Nutritional Education with the Media
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 277
Explosion Box on Knowledge and Attitudes about Anemia to Teenage Girl in Senior High
School 23 Jakarta Barat. 2019;
8. Marimbi, H. Tumbuh Kembang, Status Gizi, dan Imunisasi Dasar pada Balita. Yogyakarta :
Nuha Offset. 2010.
9. Welasasih BD, Wirjatmadi RB. Beberapa faktor yang berhubungan dengan status gizi balita
stunting. The Indonesian Journal of PublicHealth. 2012; Vol 8 Nomor 3.
10. Kholid, Ahmad. Promosi Kesehatan : Dengan Pendekatan Teori Perilaku, Media, dan Aplikasi
untuk Mahasiswa dan Praktisi Kesehatan. Jakarta : Rajawali Pers. 2014.
11. Achadi, Umar Fahmi. Kesehatan Masyarakat : Teori dan Aplikasi. Jakarta : Raja Grafindo
Persada. 2013.
12. Tentama F, Delflores HDL, Wicaksono AE, Fatonah SF. Penguatan Keluarga sebagai Upaya
Menekan Angka Stunting dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK). Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada
Masyarakat. 2018; Volume 2 Nomor 1. ISSN: 2088 4559
13. Sunarsih, Tri. Asuhan kehamilan untuk kebidanan. Jakarta: Salemba Medika. 2011.
14. Paratmanitya, Yhona. Hadi, Hamam. Susetyowati. Citra tubuh, asupan makan, dan status gizi
wanita usia subur pranikah. Jurnal Gizi Klinik Indonesia. 2012;Volume 8 Nomor 3 Halaman
126-134.
15. Sujiono, Bambang & Sujiono, Yuliani Nurani. Persiapan dan Saat Kehamilan. Jakarta : PT
Elex Media Computindo 5. 2004.
16. Susilowati, Kuspriyanto. Gizi Dalam daur Kehidupan. Bandung : PT. Refika Aditama. 2016.
17. Senbajo IO, Olawiyola IO, Senbajo OC. Maternal and Child Under Nutrition in Rural and
urban Communities of Lagos State, Nigeria : The Relationship and Risk Factor. BMC Research
Notes. 2013; ISSN : 1756-0500.
18. Prabandari, Yunilla. Hubungan Kurang Energi Kronik dan Anemia pada Ibu Hamil dengan
Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan Di Kabupaten Boyolali. Penelitian Gizi dan Makanan: 2016;
Volume 39 Nomor 1 Halaman 1-8.
19. Marlapan S, Wantouw B, Sambeka J. Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Anemia pada
Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Tuminting Kec. Tuminting Kota Manado. ejournal
keperawatan (e-Kp): 2013; Volume 1 Nomor 1.
20. Citrakesumasari, Dwi Susilowati, Suriah, Bohari. MAPPACCI sebagai Pendekatan Pemberian
Pemahaman Calon Pengantin tentang Anemia Gizi dan Kurang Energi Kronik (KEK) Di
Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI. 2012; ISSN : 978-602-235-256-3.
21. Zahraini, Y. 1000 Hari Pertama Kehidupan : Mengubah Hidup, Mengubah Masa Depan. Subdit
Bina Gizi Makro. 2013. Diakses dari http://gizi.depkes.go.id/1000-hari-mengubah-hidup-
mengubah-masa-depan pada tanggal 23 April 2019.
22. Mubarak & Chayatin. Teori dan Aplikasi Ilmu Kesehatan Masyarakat,Pendidikan Kesehatan,
Konsep Perilaku dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Salemba Medika. 2009.
23. Kumboyono. Perbedaan Efek Penyuluhan Kesehatan Menggunakan Media Cetak dengan
Media Audio Visual terhadap Peningkatan Pengetahuan Pasien Tuberkulosis. Jurnal Ilmiah
Kesehatan Keperawatan. 2011; Volume 7 Nomor 1.
24. Andriani.Wa Ode Sri, dkk. Perbedaan pengetahuan, sikap, dan motivasi ibu sesudah diberikan
program Mother Smart Grounding (MSG) dalam pencegahan Stunting di Wilayah Kerja
Puskesmas Puuwatu Kota Kendari tahun 2017. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan
Masyarakat. 2017; Volume 2 Nomor 6.
25. Maelafitri N, Laras S, Anugrah N. The Effect of Nutritional Education with the Media
Explosion Box on Knowledge and Attitudes about Anemia to Teenage Girl in Senior High
School 23 Jakarta Barat. 2019;
26. Wawan & Dewi. Teori & Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia. Yogyakarta:
Nuha Medika. 2011.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 278
27. Marchianti ACN, Sakinah EN, Diniya N. Efektifitas penyuluhan gizi pada kelompok 1000
HPK dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap kesadaran gizi. Journal of Agromedicine and
Medical Sciences. 2017; Volume 3 Nomor 3.
28. Dalyono, Muhammad. 2007. Psikologi Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta. 2007.
29. Ganiajri, Faqihani dkk. 2011. Perbedaan Pemanfaatan Multimedia Flash dan Ceramah sebagai
Media Pendidikan Reproduksi Remaja pada Remaja Awal di SMP N 3 Turi Kabupaten
Sleman. Jurnal Kesehatan Masyarakat. 2017; Volume 1 Nomor 2.
30. Gloria, Angeline. Pengaruh Penyuluhan Kesehatan dengan Metode Ceramah dan Diskusi
Kelompok terhadap Pengetahuan dan Sikap Mengenai Kesehatan Reproduksi Remaja. 2014;
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 279
KORELASI FREKUENSI SENAM HAMIL DENGAN LAMA PERSALINAN
KALA II DI RUMAH SAKIT UMUM YK MADIRA PALEMBANG TAHUN 2020
Erma Puspita Sari
1, Rini Gustina Sari
2*
1Bagian Kebidanan Universitas Kader Bangsa
2Bagian Kebidanan Universitas Kader Bangsa
Jln. Mayjend H.M Ryacudu No 88 Palembang
Corresponding email : [email protected]
THE CORRELATION BETWEEN THE FREQUENCY OF PREGNANCY EXERCISE AND
THE DURATION OF THE SECOND STAGE OF LABOR AT THE YK MADIRA
PALEMBANG GENERAL HOSPITAL IN 2020
ABSTRACT
The delivery process is influenced by five reasons, three main reasons, namely the power to expel the fetus
(power), namely contraction of the uterine muscles, contraction of the abdominal wall muscles, contraction
of the thoracic diaphragm and ligaments, other causes are the fetus and the birth canal. Of the five factors
that influence the delivery process, only the power factor can be controlled, namely routine pregnancy
exercise classes, so that prolonged labor can be prevented. The purpose of this study was to determine the
correlation between the frequency of pregnancy exercise and the second stage of labor at YK Madira
General Hospital. The research method used was quantitative, using an observational study with a
retrospective approach. The population was all post partum mothers, amounting to 20 respondents who met
the inclusion and exclusion criteria, while the study sample used the Probability Sampling Technique (not
random) with purposive sampling (criteria determined by the researcher). Analysis of the data using the
Simple Linear Regression Correlation Test, the results obtained a p value of 0.037 ≤ 0.05, meaning that there
is a proven correlation between the frequency of pregnancy exercise and the duration of the second stage of
labor. Then also obtained the pearson correlation value -0.662 which gives an interpretation that the
correlation between the frequency of exercise and the length of labor has a strong degree and has a negative
pattern, meaning that the more routine the mother does pregnancy exercises, the easier it is for the mother to
go through the normal labor process. There is a correlation between the frequency of pregnancy exercise
and the duration of the second stage of labor at the YK Madira Palembang General Hospital in 2020. It is
hoped that health workers can motivate pregnant women to participate in pregnancy exercise classes which
aim to make it easier for mothers to go through the normal labor process.
Keywords: Frequency of Pregnant Exercise, Duration of Second Stage Labor
ABSTRAK
Proses melahirkan dipengaruhi oleh lima sebab, tiga sebab utama yaitu kekuatan mengeluarkan janin (power)
yaitu kontraksi otot rahim, kontraksi otot-otot dinding perut, kontraksi thoracic diaphragma dan ligamentum,
sebab lain adalah janin dan jalan lahir. Dari kelima faktor yang mempengaruhi proses persalinan hanya faktor
power yang dapat dikontrol, yaitu rutin mengikuti kelas senam hamil, sehingga persalinan lama dapat
dicegah. Tujuan penelitian ini diketahuinya korelasi frekuensi senam hamil terhadap proses persalinan kala II
diRumah Sakit Umum YK Madira. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, menggunakan studi
observasional dengan pendekatan Retrospektif. Populasi yaitu keseluruhan ibu post partum yaitu berjumlah
20 responden yang memenuhi kriterian inklusi dan eksklusi, sedangkan sampel penelitian menggunakan
Teknik Probability Sampling (tidak acak) dengan purposive sampling (kriteria yang ditentukan peneliti).
Analisa data menggunakan Uji Korelasi Regresi Linier Sederhana, Hasil penelitian diperoleh nilai p.value
0,037 ≤ 0,05 artinya terbukti ada korelasi frekuensi senam hamil dengam lama proses persalinan Kala II.
Kemudian diperoleh juga nilai pearson correlation -0,662 yang memberikan interpretasi bahwa korelasi
frekuensi senam dengan lama persalinan mempunyai derajat yang kuat dan berpola negatif artinya semakin
rutin ibu melakukan senam hamil semakin mempermudah ibu melewati proses persalinan secara normal. ada
korelasi frekuensi senam hamil dengan lama proses persalinan kala II di Rumah Sakit Umum YK Madira
Palembang tahun 2020. Diharapkan pada tenaga kesehatan dapat memberikan motivasi kepada ibu hamil
untuk mengikuti kelas senam hamil yang bertujuan mempermudah ibu melewati proses persalinan secara
normal.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 280
Kata Kunci: Frekuensi Senam Hamil, Lama Proses Persalinan Kala II
PENDAHULUAN
Persalinan dapat diartikan poses pengeluaran hasil konsepsi melalui vagina yang dapat hidup
di luar. Persalinan Kala II atau kala pengeluaran yaitu dimulai dari pembukaan lengkap (10cm)
sampai bayi dilahirkan. Proses ini berlansung 90 menit bagi ibu yang melahirkan untuk pertama
kalinya dan 30 menit bagi ibu yang melahirkan lebih dari satu kali. Proses persalinan yang lama
dapat menyebabkan timbulnya masalah/penyulit bahkan kematian saat proses persalinan. Proses
persalinan lama dapat di cegah dengan rutin mengikuti senam hamil. (Sondakh, 2013).
Program Pemerintah dalam menurunkan angka kematian ibu dan mordibitas yaitu
memberikan pelayanan antenatal terpadu, seperti memberikan intervensi kesehatan yang efektif
selama kehamilan dengan kelas senam hamil. Tenaga kesehatan khususnya bidan dalam
memberikan pelayanan pada ibu hamil memiliki kewajiban untuk membimbing ibu melakukan
senam hamil sesuai dengan trimester kehamilan. Senam hamil dapat diartikan sebagai latihan olah
tubuh bagi ibu hamil yang tidak ada komplikasi/penyulit selama kehamilan untuk mempersiapkan
kondisi fisik ibu saat melahirkan dengan menjaga kondisi otot-otot panggul ibu dan persendian
yang berperan dalam proses persalinan sehingga bayi dapat keluar melalui vagina.
Sebenarnya sejarah perkembangan senam hamil di mulai pada saat Crel Vosky dan Lamaze
memperkenalkan metode psikopropilaksis. Lamaze menerapkan dengan teknik relaksasi. Sejak
hamil ibu melakukan latihan untuk mengubah pandangan tentang rasa sakit saat kontraksi, dari
pandangan negatif menjadi pandangan positif. Tahun 1996 Depkes RI mengeluarkan standar
pelayanan minimum Rumah Sakit Sayang Ibu yang terdiri dari 10 tahapan menuju perlindungan
Ibu secara terpadu dan maksimal. Sehingga, waktu kunjungan Antenatal Care diharapkan
memberikan Antenatal Edukasi, yaitu dari 10 langkah menuju perlindungan ibu secara terpadu dan
maksimal salah satunya dengan program senam hamil sebagai bentuk sayang ibu (Maryunani,
2011).
Adapun keuntungan melakukan senam hamil rutin tidak hanya memberikan kenyamanan ibu
selama kehamilan, tetapi juga memberikan banyak keuntungan dalam proses persalinan.
Keuntungan senam hamil di kala I, dapat menurunkan kejadian persalinan lama, mengurangi rasa
nyeri dan menurunkan rasa cemas ibu dalam melewati proses persalinan karena dengan mengikuti
senam hamil yang rutin dapat menyebabkan otot menjadi elastis dan ligamen di panggul, mengatur
tehnik respirasi serta memperbaiki posisi tubuh. Keuntungan senam hamil di kala II, yaitu
membantu ibu melewati proses persalinan yang normal sehingga persalinan lama dapat dicegah,
karena waktu mengikuti kelas senam hamil ibu dilatih cara mengejan dan mengatur pernapasan,
mengatur his dan relaksasi serta melatih kelenturan otot-otot dinding abdomen dan dasar panggul
sehingga mempermudah proses persalinan. Selama kala III dan kala IV senam hamil bermanfaat
mencegah terjadinya perdarahan yang berlebihan, karena waktu mengikuti latihan senam hamil ibu
di latih meningkatkan kemampuan mengkoordinasikan kekuatan kontraksi otot uterus (Dewi,
2013).
Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum YK Madira tahun 2017
jumlah kunjungan ibu hamil sebanyak 8.024 orang yang melakukan senam hamil 42 orang
(0,52%), tahun 2018 jumlah kunjungan ibu hamil 7.608 orang yang melakukan senam hamil 22
orang (0,28%), tahun 2019 kunjungan ibu hamil berjumlah 6.102 orang yang melakukan senam
hamil 27 orang (0,44%). Sedangkan jumlah persalinan pada tahun 2017 jumlah ibu bersalin 986
orang, tahun 2018 jumlah ibu bersalin 972 orang dan tahun 2019 jumlah ibu bersalin 878 orang.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 281
Tujuan penelitian ini diketahuinya korelasi frekuensi senam hamil dengan lamanya persalinan kala
II di Rumah Sakit Umum YK Madira Palembang.
METODE
Desain penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, menggunakan studi
observasional dengan pendekatan Retrospektif yaitu penelitian yang melihat ke belakang, yang
artinya data dikumpulkan dimulai dari akibat yang terjadi, kemudian dari akibat tersebut dicari
penyebabnya yang mempengaruhi akibat tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus-
September 2020 di RSU YK Madira Palembang.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu post partum di unit rawat inap Bagian
Obsterti dan Ginekologi di Rumah Sakit Umum YK Madira Palembang. Penelitian ini
menggunakan sampel sebanyak 10 yang memenuhi kriterian inklusi dan ekslusi. Pengambilan
sampel menggunakan Teknik Probability Sampling (tidak acak) dengan purposive sampling.
(kriteria yang ditentukan peneliti) Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dari
kuesioner dan data sekunder dari catatan rekam medik (CM) ibu post partum pervaginam di unit
rawat inap Bagian Obsterti dan Ginekologi di Rumah Sakit Bunda Palembang.
Pengolahan data dalam penelitian ini terdiri dari proses penyuntingan data, pengkodean data,
tabulasi data dan pembersihan data. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa
bivariat dengan Uji Korelasi Regresi Linier Sederhana. Sebelum melakukan analisis korelasi senam
hamil dengan lama persalinan Kala II menggunakan uji Korelasi Regresi Linier, maka disini
dilakukan analisis normalitas data terlebih dahulu.
HASIL PENELITIAN
Uji Normalitas
Dalam melakukan analisis regresi linier sederhana data penelitian harus di uji kenormalan
distribusinya, yang merupakan salah satu persyaratan analisis data. Uji Kolmogorov-Smirnov
bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal
atau tidak. Uji penelitian dalam hal ini menggunakan One-Sample Kolomogorov-Smirnov. Dasar
yang digunakan adalah dengan uji Asymp-sig(2-tailed) dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Jika
nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 artinya data penelitian berdistribusi normal, sebaliknya jika
nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 artinya data peneltian tidak berdistribusi secara normal.
Berikut hasil uji normalitas di terangkan pada tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Data Lama Persalinan
di RSU YK Madira Tahun 2020
Frekuensi Senam Lama Persalinan
N 10 10
Normal Parametersab Mean 3,60 80,60
Std Deviation ,699 4,949 Most Extreme Absolute ,416 ,152
Differences Positive ,284 ,098
Negative -,416 -,152
Kolmogorov-Smirnov Z 1,317 ,480 Asymp Sig (2-tailed) ,062 ,970
a. Test Distribution is Normal
b. Calculated from data
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 282
Berdasarkan Tabel 1 diatas, bahwa variabel frekuensi senam dan lama persalinan memiliki
nilai Asymp-sig(2-tailed) di atas 0,05 (frekuensi senam 0,062 dan lama persalinan 0,975) sehingga
dapat di simpulkan memiliki data yang berdistribusi normal.
Tabel 2 menunjukkan hasil analisis frekuensi senam dan lama persalinan di RSU YK Madira
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2. Hasil Analisis Data Numerik Frekuensi Senam dan Lama Proses Persalinan
di Rumah Sakit Umum YK Madira Tahun 2020
Frekuensi Senam Lama Persalinan
N Valid 10 10
Missing 0 0
Nilai Mean 3,60 80,60
Nilai Median 4,00 81,50 Mode 4 70a
Std. Deviation ,699 4,949
Variance ,489 24,489
Range 2 17 Nilai Minimum 2 70
Nilai Maximum 4 87
a. Multiple modes exixt The smallest value is shown
BerdasarkanTabel 2 diatas, diperoleh bahwa untuk variabel frekuensi senam nilai rata-rata
3,60, nilai tengah 4,00, mode 4, Standar Deviation 0,699, nilai terendah 2 dan nilai tertinggi 4,
sedangkan variabel lama persalinan nilai rata-rara 80,60, nilai tengah 81,50, mode 70, Standar
Deviation 4,949, nilai terendah 70 dan nilai tertinggi 87.
Tabel 3 menunjukkan hasil korelasi frekuensi senam hamil dengan lama proses persalinan
Kala II di Rumah Sakit Umum YK Madira Palembang dapat dilihat pada pabel dibawah ini :
Tabel 3. Korelasi Frekuensi Senam Hamil dengan Lama Proses Persalinan Kala II
di Rumah Sakit Umum YK Madira Tahun 2020
Frekuensi Senam Lama Persalinan
Frekuensi Senam Pearson Correlation 1 -,662
Sig (2-tailed) ,037
N 10 10 Lama Persalinan Pearson Correlation -,662 1
Sig (2-tailed) ,037
N 10 10
Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed)
BerdasarkanTabel 3 diatas, dapat dilihat nilai p.value = 0,037 ≤ 0,05 yang artinya
terbukti ada korelasi frekuensi senam hamil dengan lama proses persalinan kala II
kemudian diperoleh nilai r = -0,662 yang memberikan interpretasi bahwa korelasi
frekuensi senam dengan lama proses persalinan mempunyai derajat yang kuat dan berpola
negatif artinya semakin sering ibu melakukan senam, proses persalinan kala II semakin
cepat.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 283
PEMBAHASAN
Senam Ibu Hamil
Senam hamil dapat diartikan sebagai latihan olah tubuh bagi ibu hamil yang tidak ada
komplikasi/penyulit selama kehamilan untuk mempersiapkan kondisi fisik ibu saat melahirkan
dengan menjaga kondisi otot-otot panggul ibu dan persendian yang berperan dalam proses
persalinan sehingga bayi dapat keluar melalui vagina atau jalan lahir, apabila ibu tidak melakukan
senam hamil kemungkinan persalinan pada kala II menjadi lama sehingga meningkatkan terjadinya
gawat janin pada waktu persalinan (Susiloningtyas, 2013).
BerdasarkanTabel 2 diatas, diperoleh bahwa untuk variabel frekuensi senam nilai rata-rata
3,60, nilai tengah 4,00, mode 4, Standar Deviation 0,699, nilai terendah 2 dan nilai tertinggi 4,
sedangkan variabel lama persalinan nilai rata-rara 80,60, nilai tengah 81,50, mode 70, Standar
Deviation 4,949, nilai terendah 70 dan nilai tertinggi 87. Dalam hal ini berarti ada hubungan yang
signifikan frekuensi senam hamil pada ibu bersalin dengan kala II (pengeluaran) normal, dimana
nilai rata-rata senam yang dilakukan ibu hamil sebanyak 4 kali dalam seminggu dan nilai mean
untuk lama ibu bersalin di kala II adalah 80 menit. Latihan senam hamil yang diikuti selama
kehamilan secara rutin membuat tubuh menjadi relaksasi sempurna, dengan latihan kontraksi dan
relaksasi membuat elastisitas otot-otot dinding abdomen, ligament, otot-otot dasar dasar panggul
yang berhubungan dengan proses melahirkan menjadi lebih kuat, latihan senam hamil dapat
menguasai teknik-teknik pernapasan yang mempunyai manfaat penting dalam proses persalinan.
Sesuai dengan tujuan senam hamil menurut Agnesti (2009), bahwa secara umum ada lima tujuan
senam hamil yaitu : agar ibu hamil menguasai teknik pernapasan dengan baik yang bermanfaat
untuk memperlancar suplai oksigen bagi bayi dan teknik pernapasan juga membantu ibu hamil
ketika menjalani proses persalinan sehingga bisa berjalan normal.
BerdasarkanTabel 3 diatas, dapat dilihat nilai p.value = 0,037 ≤ 0,05 yang artinya terbukti
ada korelasi frekuensi senam hamil dengan lama proses persalinan kala II kemudian diperoleh nilai
r = -0,662 yang memberikan interpretasi bahwa korelasi frekuensi senam dengan lama proses
persalinan mempunyai derajat yang kuat dan berpola negatif artinya semakin sering ibu melakukan
senam, proses persalinan kala II semakin cepat.
Penelitian ini ternyata sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Maryunani senam hamil
adalah suatu latihan fisik yang penting untuk mempertahankan atau memperbaiki keseimbangan
fisik ibu hamil agar proses persalinan dapat berlangsung cepat, mudah dan aman (Maryunani,
2014).
Latihan senam hamil yang dilakukan mempunyai tujuan utama yaitu agar ibu hamil
mendapatkan kekuatan dan tonus otot yang baik, teknik respirasi yang baik sehingga proses
persalinan terutama saat persalinan kala II diperoleh power pada persalinan. (Muhimah,2010). Ibu
yang melakukan senam hamil secara teratur, memberikan keuntungan di kala II menjadi lebih
pendek, mengurangi kejadian operasi section caesarea, dan mengurangi terjadinya gawat janin pada
waktu persalinan, hal ini menunjukkan bahwa ibu hamil yang jarang mengikuti senam hamil akan
mengalami kala II yang lebih panjang atau lama dibandingkan ibu yang sering mengikuti senam
hamil. (Anggraeni, 2010).
Penelitian ini didukung penelitian terdahulu oleh Nugraeny (2019) dengan judul hubungan
keteraturan senam hamil dengan durasi persalinan kala II pada ibu bersalin diklinik Nurhayati,
yang hasilnya adalah ibu yang pertama kali melahirkan yang teratur senam hamil mengalami
persalinan cepat sebesar 37,5%, sedangkan multigravida yang teratur senam hamil mengalami
persalinan cepat sebesar 28,6%. Hasil uji statitistik chi square didapatkan nilai p.value = 0,004 < α
0,05 yang artinya ada hubungan yang signifikan senam hamil dengan durasi persalinan kala II.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 284
Hasil X2hitung=11,185 artinya bahwa ibu yang mengikuti senam hamil secara rutin cenderung
mengalami proses persalinan kala II dengan waktu yang lebih cepat jika dibandingkan dengan
ketidak teratur ibu melakukan senam hamil.
Proses melahirkan dipengaruhi oleh lima sebab, tiga sebab utama yaitu kekuatan
mengeluarkan janin (power) diantaranya his (kontraksi otot rahim), kontraksi otot-otot dinding
perut, kontraksi thoracic diaphragma dan ligamentum, sebab lain adalah janin (passager) dan jalan
lahir (passage). Dari kelima faktor yang mempengaruhi proses persalinan hanya faktor tenaga atau
power yang dapat dikendalikan, yaitu rutin mengikuti kelas senam hamil, sehingga persalinan
lama dapat dicegah. Senam selama kehamilan memberikan manfaat positif terhadap pembukaan
serviks, selain itu ditemukan secara bermakna proses melahirkan yang lebih awal dan persalinan
yang lebih singkat dibandingkan dengan yang tidak melakukan senam hamil, selain itu senam
hamil juga dapat membantu ibu bersalin sehingga dapat melahirkan tanpa kesulitan. (Sulistyawati,
2010).
Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Sari (2015) yang berjudul, hubungan
frekuensi senam hamil terhadap lama persalinan kala II di RB Rahmi Kota, hasilnya menunjukkan
ada hubungan frekuensi senam hamil dengan lama persalinan kala II di RB Rahmi berdasarkan
hasil analisis statistik yaitu diperoleh nilai p.value (0,028 < α 0,05).
Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Septaningtia (2015), dengan
judul hubungan senam hamil dengan lama proses persalinan kala II pada ibu primigravida di RSIA
Sadewa, hasil uji univariat diperoleh responden yang melakukan senam hamil secara rutin dan
melewati persalinan kala II yang berlangsung normal sebanyak 66,7%. Berdasarkan hasil uji chi
square diperoleh p.value 0,000 yang artinya terdapat hubungan senam hamil dengan lama proses
persalinan kala II.
Hal ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian Barus (2013) yang berjudul
Hubungan frekuensi senam hamil terhadap lama persalinan kala II pada ibu primigravida di RB
Rachmi, Hasil penelitian di dapatkan koefisien korelasi frekuensi senam hamil terhadap kala II
lama sebanyak 0,518 > 0,482 dengan signifikan sebanyak 0,048 sedangkan frekuensi senam hamil
dengan kala II normal sebanyak 0,538 > 0,482 dengan signifikan sebanyal 0,038. Sehingga H0 di
tolak dan Ha diterima artinya ada hubungan yang signifikan antara frekuensi senam hamil terhadap
lama persalinan kala II.
Penelitian Diarini (2015) di wilayah kerja Puskesmas Sumowono, diperoleh hasil penelitian
sebesar 88,2% yang mengikuti senam hamil teratur dan proses persalinannya spontan. Selain itu
diperoleh hasil penelitian sebesar 56,4% yang mengikuti senam hamil teratur dan proses
persalinannya tidak spontan. Hasil analisis bivariat didapatkan nilai p.value 0,000 ≤ α 0,05 artinya
terdapat hubungan yang signifikan senam hamil terhadap proses persalinan pada ibu bersalin di
wilayah kerja Puskesmas Sumowono Kabupaten semarang.
Penelitian Kabuhung (2016) di wilayah kerja Puskesmas Tanta, diperoleh bahwa ada
hubungan yang signifikan senam hamil dengan lama persalinan di Puskesmas Tanta. Ibu yang
melakukan senam hamil sebagian besar melewati persalinan secara normal dibandingkan ibu yang
tidak melakukan senam hamil rata-rata mengalami kala II lama, berdasarkan hasil penelitian
diperoleh nilai p.vaue 0,000 ≤ α 0,05.
Nilai korelasi berdasarkan hasil penelitian di RSU YK Madira Palembang melalui uji
korelasi dan regresi linier sederhana diperoleh sebesar -0,662 dengan nilai p.value 0,037 ≤ α 0,05,
berdasarkan tabel hubungan antara variabel memperlihatkan arah korelasi negatif yang artinya
dapat disimpulan bahwa semakin rutin ibu melakukan senam hamil maka proses persalinan akan
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 285
semakin cepat sedangkan semakin jarang ibu melakukan senam hamil maka proses persalinan
akan semakin lama.
Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan di Rumah Sakit Umum YK Madira, Ibu yang
melakukan senam hamil secara rutin, terbukti dapat mempercepat proses ibu bersalin dengan durasi
yang normal dibandingkan dengan yang melakukan senam hamil secara tidak rutin, yang artinya
ada hubungan yang signifikan antara keteraturan mengikuti senam hamil dengan durasi ibu
melahirkan, sehingga diharapkan ibu hamil lebih termotivasi mengikuti senam hamil secara rutin
dipelayanan kesehatan dengan tujuan bisa melewati proses persalinan secara normal. Rata-rata ibu
dalam penelitian ini melakukan senam hamil secara rutin, proses persalinan kala II berlansgung
singkat, sehingga dapat disimpulkan bahwa ibu yang rutin melakukan senam hamil maka lama
persalinan pada kala II akan berlangsung normal.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan analisis, maka dapat disimulkan ada hubungan yang signifikan antara frekuensi
senam hamil dengan lamanya persalinan kala II di Rumah Sakit Umum YK Madira tahun 2020, hal
ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi yang menunjukkan bahwa
nilai p.value = 0,037 ≤ 0,05 yang artinya terbukti ada korelasi frekuensi senam hamil dengan lama
proses persalinan kala II kemudian diperoleh nilai r = -0,662 yang memberikan interpretasi bahwa
korelasi frekuensi senam dengan lama proses persalinan mempunyai derajat yang kuat dan berpola
negatif artinya semakin sering ibu melakukan senam, proses persalinan kala II semakin cepat.
Sarannya diharapkan bagi tenaga kesehatan agar terus mempertahankan dalam memberikan
penyuluhan kesehatan pada masyarakat tentang pentingnya senam hamil dengan cara lebih
memotivasi ibu hamil untuk melakukan senam hamil mengingat senam hamil dapat melatih
pernapasan dan melenturkan elastisitas otot-otot rahim sehingga membantu proses persalinan dapat
berjalan dengan lancar. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian secara
eksperimen dengan pendekatan waktu prospektif.
DAFTAR PUSTAKA
1. Achadi, Endang L. 2019. ―Kematian Maternal Dan Neonatal Di Indonesia.‖ Rakerkernas
2019: 1–47.
2. Agnesti, renvilia dkk. 2009. Senam Hamil Praktis. Yogyakarta: Media Pressindo
3. Anggraeini, P. 2010. Serba-serbi senam hamil. Yogyakarta : Intan Media
4. Asrinah, dkk. 2010. Asuhan Kebidanan Masa Kehamilan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
5. Artikel PT Johnson & Johnson Indonesia.
2015. https://www.johnsonsbaby.co.id/artikel/pilihan-olahraga-yang-aman-untuk- trimester-
3-kehamilan
6. Barus, E. A., & Sarwinanti, S. (2013). Hubungan Frekuensi Senam Hamil dengan Lama
Persalinan Kala II pada Ibu Primipara di RB Rachmi Yogyakarta Tahun 2013 (Doctoral
dissertation, STIKES'Aisyiyah Yogyakarta).
7. Dewi, dkk. 2013.Asuhan kehamilan untuk kebidanan. Jakarta: Salemba Medika
8. Diarini, Dwi Okta, dkk. 2015. Hubungan Antara Senam Hamil Dengan Proses
Persalinanpada Ibu Bersalin di Wilayah Kerja Puskesmas Sumowono. Semarang: Stikes
Ngudi Waluyo Ungaran.
9. Dinas Kesehatan Kota Palembang. 2019. Laporan Tahunan Seksi Kesehatan Keluarga.
Palembang.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 286
10. Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan. 2019. Laporan Tahunan Seksi Kesehatan
Keluarga. Palembang.
11. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. 2015. Profil Kesehatan Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2014. Palembang.
12. ———. 2018. Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017. Palembang
13. Haswita, S. 2012. Hubungan motivasi ibu hamil dengan pelaksanaan senam hamil di dusun
Krajan Desa Jambewangi Wilayah Kerja Puskesmas Sempu Banyuwangi tahun 2012
14. Hidayat, A Azis Alimul. 2014. Metode Penelitian Kebidanan Dan Teknik Analisis Data.
Jakarta: Salemba Medika
15. Kabuhung, E. I., Yunita, L., & Sinaga, R. (2017). Hubungan senam hamil dengan persalinan
pada ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas Tanta Tahun 2016. DINAMIKA
KESEHATAN: JURNAL KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN, 8(1), 11-18.
16. Maryunani, Ani. 2011. Senam Hamil, senam Nifas dan Terapi Musik. Jakarta : CV Trans
Info media
17. Muhimah. 2010. Senam sehat selama kehamilan. Jakarta : Alfabeta
18. Nugraeny, L., Sumiatik, S., & Aritonang, J. (2020). Hubungan Keteraturan Senam Hamil
dengan Durasi Persalinan Kala II pada Ibu Bersalin di Klinik Nurhayati Tahun
2019. JOURNAL OF HEALTHCARE TECHNOLOGY AND MEDICINE, 6(1), 76-84.
19. Nugroho, Taufan. 2014. Patologi Kebidanan. Yogyakarta : Nuha Medika.
20. Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rineka Medika
21. Prawirohardjo, Sarwono. 2016. Ilmu Kebidanan. Jakarta: Bina Pustaka
22. Putri, Shinta. 2014. Panduan Senam Hamil. Jakarta : Platinum
23. Sari, T. P., Mindarsih, E., & Hartini, C. M. W. (2016). Hubungan frekuensi senam hamil
dengan lama persalinan kala II di RB Rahmi Kota Yogyakarta Tahun 2015. Medika Respati:
Jurnal Ilmiah Kesehatan.
24. SDG‘s. 2017. ―Sustainable Development Goals
25. Septaningtia, Y. D., & Anjarwati, A. (2015). Hubungan Senam Hamil dengan Lama Proses
Persalinan Kala II pada Ibu Primigravida di RSKIA Sadewa Yogyakarta (Doctoral
dissertation, STIKES'Aisyiyah Yogyakarta).
26. Sondakh, .J.S. 2013. Asuhan kebidanan persalinan danbayi baru lahir.Jakarta:Erlanga.
27. Susilonihgtyas. 2013. Serba-serbi Senam Hamil. Yogyakarta. Intan Media
28. Sulistyawati, Ari dan EstiNugraheny. 2013. Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin .Salemba
Medika: Jakarta.
29. Walyani. (2015). Asuhan kebidanan masa nifas dan menyusui. Yogyakarta: Pustaka Baru
Pres
30. World Health Organization. (2019). Levels and Trends in Child Mortality: Report
2019 (No. 141926, pp. 1-52). The World Bank.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 287
PERUBAHAN KESADARAN KESEHATAN AKIBAT PANDEMIK COVID-19
PADA MAHASISWA DI SUMATERA SELATAN
Windi Indah Fajar Ningsih
1*, Fatmalina Febry,
2 Indah Purnama Sari,
3 Ditia Fitri
Arinda4
1Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya
2Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya
Jl. Palembang Prabumulih KM. 32, Indralaya Indah Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan
Corresponding email : [email protected]
THE CHANGES OF HEALTH AWARENESS DUE TO COVID-19 PANDEMIC
OUTBREAK AMONG COLLEGE STUDENTS IN SOUTH SUMATERA
ABSTRACT
COVID-19 pandemic is a problem facing in the world today. Efforts were made to suppress the spread of
SARS-CoV-2 as a cause of it. The implementation of health protocols are one of them. South Sumatra has an
urge implementing the protocols considering for 6 months its pandemic status is still in the red zone.
Students are youth who are able to access information regarding health protocols. During pandemic, they
are expected to apply the health protocols so that they can contribute stopping the spread of COVID-19. This
study aims to see the health awareness changes influenced by COVID-19 pandemic among students in South
Sumatra. The study design of the research was observational with the cross-sectional method through online
survey conducted in August 2020. Samples were obtained by non-random sampling, with inclusive
criteriums: college students in South Sumatra, aged 18-24 years, attended the research and completed
questionnaires. There were 612 students participated. Univariate analysis was carried out for respondents
answers in the form of percentage. There were 91.2% respondents lived in their own house during pandemic
compared while before lived in boarding houses. More than 80% of health awareness was implemented
except physical activity which did not change much than before the pandemic. Wearing masks had been
carried out by 99.5% of respondents. There have been positive attitude changes among students in South
Sumatra related to health awareness due to the outbreaks. It has become a form of community effort to obey
health protocols and protect themselves from COVID-19.
Keywords: Primary dysmenorrhea, female students, senior high school
ABSTRAK
Pandemi COVID-19 menjadi permasalahan yang dihadapi dunia saat ini. Berbagai upaya dilakukan untuk
menekan penyebaran virus SARS-Cov-2 sebagai penyebab pandemi. Penerapan protokol kesehatan
merupakan salah satu solusinya. Sumatera Selatan memiliki urgensi dalam penerapan hal tersebut mengingat
selama 6 bulan status pandeminya masih berada di zona merah. Mahasiswa merupakan golongan usia muda
yang mampu mengakses informasi mengenai protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 dan diharapkan
menerapkannya sehingga bisa berkontribusi dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Penelitian
ini bertujuan untuk melihat perubahan sikap terkait kesadaran kesehatan akibat pandemi COVID-19 pada
mahasiswa di Sumatera Selatan. Desain penelitian yang digunakan adalah observasional dengan metode
potong lintang melalui survei online yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2020. Sampel didapat secara non
random sampling yaitu mahasiswa perguruan tinggi di Sumatera Selatan, berusia 18-24 tahun, bersedia
mengikuti penelitian dan menyelesaikan pengisian kuesioner, sebanyak 612 mahasiwa/i berpatisipasi.
Analisis univariat dilakukan dan disajikan dalam bentuk tabel persentase jawaban responden. Sebanyak
91,2% responden tinggal di rumah orang tua selama pandemik COVID-19 dibanding sebelumnya tinggal di
kos. Lebih dari 80% kesadaran kesehatan diterapkan kecuali aktivitas fisik yang tidak banyak berubah dari
sebelum ke saat pandemik COVID-19. Kesadaran menggunakan masker sudah dilakukan 99,5% responden.
Terdapat perubahan sikap positif pada mahasiswa di Sumatera Selatan terkait kesadaran kesehatan akibat
pandemi COVID-19. Perubahan tersebut menjadi bentuk usaha masyarakat dalam mematuhi protokol
kesehatan dan melindungi diri dari COVID-19.
Kata Kunci: COVID-19, kesehatan, aktivitas fisik, Sumatera Selatan
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 288
PENDAHULUAN
Organisasi Kesehatan Dunia, WHO telah mengumumkan secara resmi bahwa mereka telah
mengidentifikasi coronavirus jenis baru pada Januari 2020 yang diberi nama 2019-nCoV.
Keberadaan virus ini pertama kali dilaporkan pada Desember 2019 terjadi di Wuhan, China. 2019-
nCov ini banyak dikenal dengan sebutan Covid-19 yaitu virus yang disebabkan oleh Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Virus tersebut menyerang saluran
pernafasan dengan menyebar melalui carrier tanpa bergejala, bergejala awal dan bergejala (1) .
Pada akhir Juni 2020 sejumlah besar kasus Covid-19 secara global terjadi melebihi 10 juta kasus
sehingga WHO menetapkan kejadian ini sebagai pandemi.
Pandemi COVID-19 menjadi permasalahan yang dihadapi dunia saat ini. Berbagai upaya
dilakukan untuk menekan penyebaran virus SARS-Cov-2 yang menyebar cepat melalui droplet
yang keluar saat berbicara, batuk ataupun bersin saat berinteraksi dan saling berhadapan (1).
Temuan terbaru juga menyatakan bahwa toilet berpotensi menjadi tempat transmisi SARS-CoV-2
setelah dideteksi keberadaannya pada kloset dan wastafel yang telah digunakan oleh pasien positif
COVID-19 dengan gangguan saluran pernapasan atas ringan (2). Pemerintah melakukan berbagai
upaya untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini salah satunya adalah pengambilan
kebijakan di bidang pendidikan berupa kebijakan belajar dari rumah (3) .Mahasiswa salah satu
yang mengalami dampak kebijakan ini sehingga kegiatan belajar mengajar perkuliahan dilakukan
secara daring. Penelitian menunjukan bahwa dampak pandemic COVID-19 dialami oleh
mahasiswa dimana mahasiswa lebih banyak melakukan kegiatan sedentari, mengalami peningkatan
kecemasan dan gejala depresi (4) .
Saat ini berbagai upaya dilakukan oleh ilmuan dalam mengembangkan vaksin untuk
pengobatan infeksi COVID-19 . Berbagai negara melakukan aksi kesehatan dalam rangka
mencegah peningkatan kasus COVID-19 dan sebelum vaksin yang benar- benar teruji efektif
ditemukan, maka penyebaran COVID-19 diupayakan untuk dicegah melalui serangkaian usaha
promosi kesehatan yang disebarkan melalui berbagai media seperti televisi, surat kabar dan
platform media sosial. Propaganda kesehatan terkait COVID-19 melalui berbagai media dan
pengembangan edukasi promosi kesehatan sangat diperlukan untuk memperbaiki prilaku tidak
sehat baik pada orang kota maupn desa (5). Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah
mengeluarkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) (6) serta
promosi kesehatan yang dilakukan secara masif. Indonesia sebagai salah satu negara yang
mengalami dampak besar akibat infeksi Covid-19 ini memiliki jumlah kasus 299.506 per 3 Oktober
2020. Jumlah kasus yang terus meningkat berdampak pada keluarnya kebijakan larangan pada
beberapa negara seperti Malaysia, India, dan Amerika Serikat agar WNI tidak mengunjungi negara
mereka saat ini begitupun warga negara mereka yang ingin berkunjung ke Indonesia(7). Hal ini
menyebabkan Indonesia mempunyai urgensi dalam pengendalian pandemi ini. Sumatera Selatan
sebagai bagian di dalamnya juga memiliki urgensi untuk melakukan pengendalian tersebut
mengingat selama 6 bulan status pandeminya masih berada di zona merah dengan total jumlah
kasus positif per 3 Oktober 2020 yaitu 6277 orang (8). Selama pandemi COVID-19 sangat penting
untuk memperbaiki pengetahuan dan kepercayaan pada masyarakat umum untuk mencegah
penyebaran infeksi COVID-19 (9).
COVID-19 memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi,
politik hingga pendidikan. Hal ini dikarenakan salah satu upaya pencegahan menyebarnya COVID-
19 melalui aksi personal yaitu menjaga jarak, menerapkan personal higiene, dan menggunakan alat
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 289
proteksi diri, tetap di rumah, membatasi menggnakan transportasi umum yang dikampanyekan di
berbagai media promosi. Perubahan tersebut menghasilkan pembatasan aktivitas normal,
pariwisata, hingga aktivitas latihan fisik seperti ditutupnya klub kebugaran dan ditiadakannya
pertemuan karena peningkatan aksi menjaga jarak/ social distancing (10). Orang – orang secara
aktif mempelajari dan memperoleh informasi terkait COVID-19 melalui berbagai saluran TV,
website (11). Mahasiswa merupakan golongan usia muda yang paling banyak memanfaatkan media
sosial dalam kehidupan sehari – harinya sehingga mereka mampu mengakses informasi mengenai
upaya agar terhindar dari paparan COVID-19. Protokol kesehatan yang dipromosikan selama
pandemi COVID-19 akan sering mereka jumpai sehingga diharapkan mereka dapat menerapkannya
sehingga bisa berkontribusi dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hal ini juga
sesuai dengan (12) yang menyatakan bahwa golongan usia muda memiliki kemampuan mengakses
informasi yang lebih cepat daripada golongan orang tua sehingga risiko terpapar COVID-19 lebih
rendah dibanding orang tua. Mahasiswa menunjukan persepsi positif dalam pencegahan dan control
COVID-19, mahasiswa kesehatan sesuai dengan pendidikan dan pemahaman dasar mereka dapat
berperan penting dalam meningkatkan kesadaran keseriusan pandemi COVID-19 di kalangan
masyarakat (9).
METODE
Penelitian ini menggunakan desain observasional dengan metode potong lintang. Data pada
penelitian ini berupa kuisioner yang diunggah dan disebarkan secara online menggunakan Google
form dengan link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNPmHp5jyW88FpREuSSCb16Hyw4Sgo9H1
IPcFY8dNDiaABg/viewform yang dibagikan secara meluas melalui rekan dan kolega yang ada di
17 kabupaten/kota di seluruh Sumatera Selatan dengan undangan pengisian melalui WhatsApp,
Instagram, dan E-mail. Akses pengisian dibuka selama 1 bulan Agustus 2020. Kuisioner online
berisi 7 pertanyaan terkait karakteristik diri dan 16 pertanyaan terkait kesadaran kesehatan.
Pertanyaan terkait kesadaran kesehatan dikembangkan berdasarkan protokol kesehatan yang
dikeluarkan oleh Kemenkes RI (6). Pertanyaan tersebut berkaitan dengan bagaimana perilaku
penerapan protokol kesehatan serta upaya menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh dari paparan
COVID-19. Pertanyaan pada kuisioner online tersebut disajikan dalam bentuk yang mudah
dipahami responden dan harus dijawab langsung dengan format pertanyaan kebiasaan ―sebelum
dan selama‖ pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan sikap terkait
kesadaran kesehatan akibat pandemi COVID-19 pada mahasiswa di Sumatera Selatan. Sampel
diperoleh secara non random sampling dengan kriteria inklusi meliputi mahasiswa perguruan tinggi
di Sumatera Selatan, berusia 18-24 tahun, bersedia mengikuti penelitian, dan menyelesaikan
pengisian kuisioner. Sebanyak 633 orang terlibat dalam pengisian kuisioner namun hanya sebanyak
612 data yang memenuhi syarat pengolahan data. Analisis univariat dilakukan serta disajikan
dalam bentuk tabel berisi persentase jawaban responden. Penelitian ini sudah mendapat telaah dan
ijin etik dari komisi etik FKM Unsri dengan nomer kode etik No:196/UN9.1.10/KKE/2020.
HASIL PENELITIAN
Karakteristik responden disajikan dalam tabel 1 berdasarkan usia, jenis kelamin, asal
perguruan tinggi, rumpun program studi, domisili sebelum dan saat pandemi, dan keikutsertaan uji
tes COVID-19. Total sebanyak 612 responden berpartisipasi dalam penelitian ini dengan responden
berusia 17-24 tahun, mayoritas responden adalah perempuan 78,8 %. Responden berasal dari
berbagai perguruan tinggi di Sumatera Selatan dengan mayoritas berkuliah di rumpun program
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 290
studi kesehatan dan kedokteran (43,6 %) diikuti oleh ilmu pendidikan (24,8 %). Sebanyak 91,2 %
responden tinggal di rumah orang tua selama pandemi COVID-19 dibanding sebelum pandemi
sejumlah 46,2 %. Mayoritas responden yaitu sebanyak 95,1 % belum pernah melakukan pengujian
tes COVID-19.
Tabel 1. Karakteristik Responden
Karakteristik Total Responden
n %
Usia
17 tahun 1 0,2
18 tahun 59 9,6 19 tahun 144 23,5
20 tahun 182 29,7
21 tahun 145 23,7
22 tahun 61 10 23 tahun 15 2,5
24 tahun 5 0,8
Jenis Kelamin
Laki-laki 130 21,2 Perempuan 482 78,8
Asal Perguruan Tinggi
Universitas Sriwijaya 267 43,6
Universitas PGRI Palembang 73 11,9 Multi Data Palembang 1 0,2
UIN Raden Fatah 65 10,6
Polsri 54 8,8
STAI OKI 2 0,3
Poltekkes Kemenkes Palembang 20 3,3
STAI Baturaja 7 1,1
Universitas Taman Siswa Palembang 10 1,6
Akbid Nusantara Indonesia Linggau 9 1,5 STIKES Pembina Palembang 8 1,3
STIKES Muhammadiyah Palembang 20 3,3
Universitas Terbuka Palembang 1 0,2
Universitas Sjakhyakirti 7 1,1 Universitas Tridinanti 4 0,7
AKPER Pembina Palembang 1 0,2
Poltekpar Palembang 11 1,8
STIK Bina Husada Palembang 2 0,3 STIK Siti Khadijah Palembang 5 0,8
STIKES Mitra Adiguna Palembang 4 0,7
Universitas IGM Palembang 1 0,2
Universitas Kader Bangsa Palembang 4 0,7 Universitas Islam OKI 2 0,3
Universitas Musi Rawas 11 1,8
Universitas Palembang 3 5
Universitas Muhammadiyah Palembang 20 3,3
Rumpun Program Studi
Kesehatan & Kedokteran 267 43,6
Non-Kesehatan (Sains dan Teknologi) 60 9,8
Ilmu Sosial 27 4,4 Ilmu Agama 5 0,8
Ilmu Pendidikan 152 24,8
Lainnya 101 16,5
Domisili/Tempat Tinggal (Sebelum
COVID-19)
Rumah Orang Tua 300 49
Kos/Asrama 283 46,2
Rumah Kerabat 28 4,6
Lainnya 1 0,2
Domisili/Tempat Tinggal (Saat COVID-
19)
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 291
Tabel 2.
Perubahan Kesadaran Kesehatan Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19
No Variabel Sebelum COVID-19 Saat COVID-19
n % n %
1. Anda selalu menggunakan masker ketika bepergian
a. Ya 304 49,7 609 99,5
b. Tidak 308 50,3 3 0,5
2. Anda selalu menutup mulut dan hidung ketika batuk dan bersin
a. Ya 564 92,2 606 99
b. Tidak 48 7,8 6 1,00
3. Anda selalu menjaga jarak minimal 1 meter
dengan lawan bicara
a. Ya 66 10,8 566 92,5
b. Tidak 546 89,2 46 7,5 4. Anda selalu mencuci tangan sebelum makan,
setelah batuk atau bersin, setelah memegang
benda, atau setelah dari luar rumah
a. Ya 497 81,2 603 98,5
b. Tidak 115 18,8 9 1,5
5. Anda membersihkan tangan dengan cara
a. Air saja 177 28,9 5 0,8 b. Air dengan sabun 396 64,7 510 83,3
c. Hand sanitizer 28 4,6 94 15,4
d. Tisu basah 11 1,8 3 0,5
6. Apakah Anda selalu mandi dan mengganti pakaian setelah bepergian
a. Ya 340 55,6 577 94,3
b. Tidak 272 44,4 35 5,7
7. Apakah Anda menyempatkan diri untuk berjemur setiap pagi
a. Tiap hari 104 17 232 36,4
b. Seminggu 1x 234 38 182 29,7
c. Seminggu 2x 110 18 100 16,3 d. Seminggu 3x 22 3,6 58 9,5
e. Tidak melakukan 142 23,2 49 8
8. Pukul berapakah biasanya Anda berjemur
a. 07.00-10.00 370 60,5 381 62,3
b. 10.00-11.00 89 14,5 171 27,9
c. 11.00-12.00 3 0,5 6 1
d. >12.00 10 1,6 5 0,8
e. Tidak melakukan 140 22,9 49 8 9. Berapa lama durasi Anda berjemur
a. <10 menit 277 45 200 32,7
b. 10-20 menit 165 27 312 51
c. >20 menit 27 4,4 49 8 d. Tidak melakukan 143 23,4 51 8,3
10. Bagaimana Anda mengakses makanan sehari-
hari
a. Masakan rumahan 411 67,2 591 96,6 b. Membeli di luar 201 32,8 21 3,4
11. Apakah Anda mengonsumsi
Rumah Orang Tua 558 91,2 Kos/Asrama 34 5,6
Rumah Kerabat 19 3,1
Lainnya 1 0,2
Mengikuti Uji Tes COVID-19 Ya, rapid test 28 4,6
Ya, swab test 2 0,3
Tidak pernah 582 95,1
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 292
suplemen/vitamin minimal 1 minggu a. Ya 264 43,1 403 65,8
b. Tidak 348 56,9 209 34
12. Suplemen yang dikonsumsi (saat COVID-19)
Vitamin C 286 51 360 49 Lainnya 274 49 376 51
13. Apakah Anda mengonsumsi ramuan
tradisional minimal 1 minggu sekali
a. Ya 161 26,3 252 41,2 b. Tidak 451 73,7 360 58,8
14. Apakah Anda melakukan olahraga secara
rutin minimal 30 menit setiap hari
a. Ya 192 31,4 302 49,3 b. Tidak 420 68,8 310 50,7
15. Lama waktu yang Anda gunakan untuk
mengerjakan tugas/kuliah di depan laptop
a. <1 jam / hari 62 10,1 54 8,8 b. 1-2 jam 213 34,8 167 27,3
c. 3-4 jam 229 37,4 198 32,4
d. 5-6 jam 64 10,5 98 16
e. >6 jam 44 7,2 95 15,5 16. Berapa lama waktu luang yang Anda miliki
dan dapat digunakan untuk bersantai dalam
sehari
a. <1 jam/hari 53 8,7 30 4,9 b. 1-2 jam 235 38,4 109 17,8
c. 3-4 jam 324 52,9 473 77,3
TOTAL 612 100 612 100
Penelitian ini mencari tahu perubahan sikap terkait kesadaran kesehatan akibat pandemi
COVID-19 pada mahasiswa di Sumatera Selatan dengan menanyakan sikap dan perilaku kesehatan
sebelum dan saat pandemi COVID-19 yang disajikan pada tabel 2. Kesadaran dalam menerapkan
protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menutup mulut dan hidung saat bersin, menjaga
jarak, mencuci tangan, dan mandi setelah bepergian menunjukkan adanya peningkatan kesadaran
kesehatan dari sebelum dan saat pandemi COVID-19. Persentase penggunaan masker ketika
bepergian mencapai 99,5 % selama pandemi COVID-19, perilaku menutup mulut dan hidung saat
bersin tidak banyak mengalami perubahan dari sebelum hingga selama pandemi yaitu 92,2 %
menjadi 99 %. Perubahan yang drastis terlihat pada perilaku menjaga jarak minimal 1 meter di
mana sebelum pandemi COVID-19 hanya 10,8 % responden yang melakukan namun bertambah
menjadi 92,5 % selama pandemi. Perilaku mencuci tangan hanya tidak dilakukan oleh 1,5 %
responden dan pilihan terbanyak cara mencuci tangan adalah dilakukan dengan sabun oleh 83,3 %
responden. Setengah dari responden (55,6 %) selalu mandi dan mengganti pakaian setelah
bepergian sebelum pandemi namun persentasenya bertambah di mana saat pandemi 94,3 %
responden melakukan hal tersebut. Upaya lain yang dapat dilakukan dalam melindungi diri dari
infeksi COVID-19 yaitu dengan meningkatkan daya tahan tubuh dengan berjemur, mengonsumsi
makanan bergizi, mengonsumsi vitamin maupun suplemen kesehatan, dan melakukan aktivitas
fisik. Kegiatan berjemur dilakukan oleh 36,4 % responden selama pandemi COVID-19 yang
dominan dilakukan pada pukul 07.00 hingga 10.00 selama 10-20 menit setiap harinya. Selama
pandemi COVID-19, responden lebih banyak mengakses makanan dengan cara mengonsumsi
makanan rumahan (96,6 %). Selain itu, terdapat peningkatan konsumsi suplemen/vitamin yang
dilakukan oleh responden selama pandemi yaitu sebesar 22,7 % dari sebelum pandemi. Hal
tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan sikap yang positif pada mahasiswa di Sumatera
Selatan terkait kesadaran kesehatan akibat pandemi COVID-19. Perubahan tersebut menjadi bentuk
usaha masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dan melindungi diri dari COVID-19.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 293
Penelitian lain sudah banyak menunjukkan bahwa orang-orang sudah mengetahui dan menyatakan
bahwa cara untuk mencegah infeksi COVID-19 dapt dilakukan dengan olahraga rutin, makan
makanan bergizi, mengubah gaya hidup, berjemur di bawah sinar matahari, tetap berada di rumah,
dan menjaga daya tahan tubuh mereka (11)(13)(14) .
PEMBAHASAN Penerapan Protokol Kesehatan
Kesadaran kesehatan diartikan sebagai sikap yang dilakukan oleh responden dalam upaya
melindungi dirinya dari infeksi COVID-19. Kesadaran kesehatan dituangkan dalam bentuk
pertanyaan dalam penerapan protokol kesehatan yang sudah dipromosikan oleh pemerintah melalui
GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan
menjaga jarak. Hasil tabel 2 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 49,8 % dalam
penggunaan masker pada saat COVID-19 yaitu sebanyak 99,5 % responden menggunakan masker
ketika bepergian pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Hasil yang serupa dinyatakan oleh (15) di
mana penggunaan masker sebagai perubahan perilaku dominan di masa pandemi. Hal ini
menunjukkan bahwa responden telah sadar akan bahaya dari penyebaran COVID-19. Selain itu,
peningkatan perilaku dalam menggunakan masker sejalan dengan penelitian Jacob dalam (16), di
mana terjadi peningkatan perilaku masyarakat dalam menggunakan masker dan mencuci tangan
hingga 84 %. Hal ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa telah memahami masker sebagai salah
satu Alat Pelindung Diri (APD) untuk menurunkan risiko infeksi COVID-19 yang masuk melalui
hidung dan mulut. Masker merupakan sistem penghalang yang efektif dalam mencegah cairan yang
berpotensi sebagai sumber infeksi (17).
Anjuran dalam menerapkan protokol kesehatan berupa menutup hidung dan mulut ketika
bersin dilakukan oleh 99 % responden selama pandemi. Menutup hidung dan mulut merupakan
salah satu tindakan pencegahan infeksi COVID-19. Hal ini dikarenakan bersin dan batuk yang
dilakukan oleh seseorang memungkinkan keluarnya droplet dan aerosol yang dapat menjadi
sumber penularan COVID-19. Penularan COVID-19 dari manusia ke manusia lain dapat terjadi
melalui penularan dari droplet maupun aerosol saat seseorang berbica, batuk, dan bersin (17) .
Perilaku menjaga jarak minimal 1 meter dilakukan oleh responden sebelum dan saat
pandemi berturut-turut sebesar 10,8 % dan 92,5 %. Hal ini penting untuk diterapkan karena selain
dapat mencegah penularan virus, menjaga jarak juga merupakan langkah untuk menurunkan angka
kejadian infeksi COVID-19. Penularan virus penyebab COVID-19 dapat terjadi akibat droplet yang
keluar saat seseorang batuk, bersin, maupun berbicara. Senada dengan hal itu, jika masyarakat
tidak menerapkan aturan menjaga jarak maka akan terjadi penambahan jumlah orang yang
terinfeksi COVID-19 (16). Selain menjaga jarak, hal lain yang dilakukan dalam upaya memutus
rantai penyebaran COVID-19 adalah dengan menghindari keramaian (18). Hasil penelitian di
Pakistan juga menunjukkan responden telah melakukan praktik jaga jarak aman untuk
menghindari infeksi COVID-19 salah satunya dengan tidak melaksanakan salat di masjid selama
pandemi COVID-19 (19).
Berdasarkan tabel 2, terdapat perubahan kebiasaan saat pandemi dalam membersihkan
tangan yaitu mencuci tangan dengan air dan sabun yang dilakukan oleh 83,3 % responden. Salah
satu promosi kesehatan melawan COVID-19 yang disebarkan oleh pemerintah adalah Cuci Tangan
Pakai Sabun (CTPS). Namun di sisi lain terdapat responden lainnya yang melakukan hal alternatif
yaitu mencuci tangan dengan air saja, hand sanitizer, serta tisu basah untuk membersihkan tangan
mereka. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang positif di mana responden
mengubah kebiasaannya yaitu mencuci tangan dengan air dan sabun untuk melindungi diri dari
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 294
infeksi COVID-19. Usaha tersebut sejalan dengan GERMAS sebagai langkah untuk
mengampanyekan perubahan gerakan masyarakat di mana program tersebut memperkenalkan
kepada masyarakat untuk sering mencuci tangan mereka dalam memperlambat penyebaran
COVID-19 (16) .
Peningkatan Daya Tahan Tubuh
Daya tahan tubuh merupakan modal individu dalam mempertahankan dirinya dari serangan
infeksi COVID-19 karena COVID-19 menyerang seseorang dengan daya tahan tubuh yang lemah.
Daya tahan tubuh dapat ditingkatkan melalui usaha-usaha yang dapat meningkatkan sistem
kekebalan tubuh. (20) Konsumsi banyak air, mineral seperti magnesium dan zink, mikronutrien,
rempah, dan makanan kaya vitamin C, D, dan E, di mana perbaikan pola konsumsi ini dapat
meningkatkan kesehatan khususnya dalam menghadapi infeksi. Tabel 2 menunjukkan adanya
peningkatan perilaku responden dalam berjemur sebesar 19,4 % jika dibandingkan dengan sebelum
pandemi. Selain itu, sebagian besar responden melakukan kegiatan berjemur setiap hari (36,4 %)
dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 (17 %). Saat pandemi COVID-19 sebagian besar
responden berjemur pada pukul 07.00-10.00 (62,3 %). Sebelum COVID-19 , sebagian besar
responden berjemur dengan durasi kurang dari 10 menit (45 %). Kegiatan berjemur tersebut
mengalami peningkatan sebesar 6 % saat pandemi COVID-19 di mana sebanyak 51 % responden
melakukan kegiatan berjemur dengan durasi 10-20 menit. Kegiatan berjemur dilakukan untuk
mendapatkan paparan cahaya matahari yang bermanfaat sebagai pemicu imunosupresi dan
memperbaiki respon imun yang rusak melalui kulit kemudian ke seluruh tubuh (21). Berbagai studi
telah menunjukkan peran penting vitamin D dalam mengatasi infeksi virus influenza melalui
kategori imunitas adaptif, penghalang fisik, dan kekebalan seluler alami
Pemenuhan makanan sehari-hari mengalami perubahan yang ditunjukkan oleh data pada
tabel 2. Kebiasaan makan seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi fisiologi, psikologi, sosial-
budaya, dan juga kondisi darurat seperti pandemi yang sedang dialami (22). Terjadi peningkatan
akses makanan rumahan yang dilakukan oleh responden sebesar 29,4 % bila dibandingkan antara
sebelum dan saat pandemi COVID-19. Sebanyak 96, 6 % responden mengakses makanan melalui
masakan rumahan untuk makan sehari-hari. Salah satu kebijakan penerapan protokol kesehatan
yang ditetapkan pemerintah pada masa pandemi ini adalah menjaga jarak dan berada di rumah. Hal
ini berdampak pada banyaknya tempat makan yang tutup maupun menerapkan sistem makanan
dibawa pulang (take away service) sehingga menimbulkan perubahan kegiatan makan di luar saat
pandemi. Kekhawatiran terhadap kualitas makanan dari luar rumah mungkin menjadi alasan akses
makanan dari luar rumah menurun selama pandemi (3,4 %). Kondisi ini juga didukung oleh
tingginya kasus positif COVID-19 yang berdampak pada mahasiswa lebih banyak pulang ke rumah
orang tua masing-masing (91,2 %) sehingga akses masakan rumahan pun menjadi lebih tinggi. Hal
ini didukung oleh pernyataan (3) bahwa mahasiswa dari berbagai daerah pulang ke kampung nya
masing-masing akibat diterapkannya program pembelajaran jarak jauh. Bahkan, kondisi ini
menjadikan India mengarahkan masyaratnya untuk melakukan pemanfaatan lahan pribadi untuk
menanam sayuran dan makan makanan yang sehat dan organik (23)
Tingkat konsumsi suplemen/vitamin pun mengalami peningkatan saat pandemi dengan
pilihan konsumsi terbanyak adalah vitamin C yaitu sebanyak 58,82 % responden. Konsumsi
suplemen/vitamin diyakini dapat meningkatkan imunitas tubuh. Vitamin/suplemen yang biasa
dikonsumsi adalah vitamin C yang telah diketahui berperan sebagai antioksidan untuk mengurangi
radikal bebas atau racun dalam tubuh manusia. Pangan fungsional berupa rempah-rempah menjadi
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 295
sorotan selama pandemi COVID-19. Berdasarkan penelitian, kandungan zat di dalamnya
merupakan komponen bioaktif yang dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh karena berperan
sebagai imunostimulator (24). Penelitian (22) menemukan bahwa jahe, kunyit, dan lemon menjadi
rempah-rempah pilihan dominan saar pandemi COVID-19. Hal tersebut berbeda dengan hasil
penelitian ini yaitu meskipun terdapat peningkatan konsumsi ramuan tradisional jika dibandingkan
sebelum dan saat pandemi yaitu sebesar 14,9 %, mahasiswa masih banyak yang memilih untuk
tidak mengonsumsinya selama pandemi COVID-19 (58,8 %). Hal ini kemungkinan dikarenakan
mahasiswa belum terbiasa mengonsumsi rempah-rempah dan tidak menyukai rasanya sehingga
diperlukan pengolahan rempah yang dapat disukai oleh semua kalangan. Berbeda dengan hal itu,
orang tua biasa mengombinasikan rempah dengan minuman lain ataupun mencampurnya dengan
makanan mereka (20). Rempah secara umum dapar dimanfaatkan sebagai bahan dalam minuman
seperti teh sehingga komponen bioaktifnya dapat dimanfaatkan (25). Menurut Xue, 2020 dalam
(20) , penggunaan rempah dalam mencegah infeksi selama pandemi juga harus menyertakan
olahraga, psikologi, pengobatan medis, dan diet
Beraktivitas fisik juga diyakini sebagai salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan sistem
imunitas tubuh. Anjuran GERMAS untuk beraktivitas fisik minimal 30 menit setiap harinya
diketahui tidak mengalami banyak perubahan pada responden sebelum dan saat pandemi COVID-
19 (17,9 %). Meskipun perkuliahan dilakukan secara daring dengan menghabiskan banyak waktu
di rumah saja, namun minat mahasiswa untuk beraktivitas fisik masih rendah (49,3 %). Pandemi
COVID-19 menyebabkan penurunan aktivitas fisik dan meningkatnya aktivitas sedentari sebagai
akibat dari anjuran menjaga jarak dan tetap di rumah (26), Penelitian ini menunjukkan adanya
penurunan level aktivitas fisik selama pandemi terutama pada laki-laki. Durasi paling lama
responden mengisi waktu dengan melakukan perkuliahan secara daring maupun mengerjakan
tugas di depan laptop adalah 3-4 jam per hari (32,4 %). Sementara itu, sebanyak 77,3 % responden
menggunakan waktu kesehariannya untuk bersantai selama lebih dari 3-4 jam saat kebijakan proses
pembelajaran jarak jauh diterapkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (10) juga menyatakan
bahwa adanya pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan aktivitas secara umum seperti gaya
hidup dan aktivitas fisik.
Secara umum penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan kesadaran kesehatan
pada mahasiswa di Sumatera Selatan baik dari segi kepatuhan menjalankan protokol kesehatan
maupun upaya meningkatkan daya tahan tubuh. Hasil ini sejalan dengan penelitian (27) yang
menyatakan bahwa sebanyak 92 % masyarakat telah memahami cara meningkatkan sistem imun
tubuh mereka. Perubahan positif tersebut dilakukan oleh responden dengan keyakinan bahwa
mengambil tindakan protektif akan mengurangi risiko terpapar COVID-19 (15). Penelitian (28)
menyatakan bahwa tuntutan psikologis akan pengetahuan dan intervensi selama pandemi COVID-
19 pada mahasiswa tinggi sehingga mereka mencari tahu informasi lebih banyak terkait COVID-19
untuk menghindari kecemasan dan depresi akan pandemi COVID-19. Kecemasan yang dihadapi
mahasiswa meliputi pilihan untuk tinggal di rumah orang tua atau yang lain, bagaimana pandemi
COVID-19 mempengaruhi penghasilan orang tua, dan apakah ada kenalan mereka yang terinfeksi
COVID-19 (29).
Kondisi pandemi COVID-19 juga tak lepas dari berita hoaks dan mitos yang beredar
sehingga sangat diperlukan program edukasi terkait pengetahuan, persepsi, dan praktik terkait
COVID-19 yang dapat dilakukan melalui media maupun jejaring sosial (30). Hal ini juga berkaitan
dengan kemampuan mengakses informasi yang mudah oleh mahasiswa sebagai golongan usia
muda. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian (31) yang menyatakan bahwa jejaring media
sosial dan televisi menjadi sumber terbesar yang diperoleh orang-orang dalam mendapatkan dan
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 296
mengadopsi informasi terkait COVID-19. Kemampuan tersebut selanjutnya membentuk kesadaran
untuk berperilaku preventif dalam melindungi diri sendiri dan memiliki persepsi risiko yang
moderat (32). Perilaku melindungi diri di publik berperan penting dalam mengendalikan
penyebaran COVID-19 (15).
KESIMPULAN DAN SARAN
Terdapat perubahan sikap positif pada mahasiswa di Sumatera Selatan terkait kesadaran
kesehatan akibat pandemi COVID-19. Perubahan kesadaran yang dilakukan yaitu menerapkan
protokol kesehatan dan melakukan upaya dalam meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah
infeksi COVID-19. Perubahan tersebut menjadi bentuk usaha masyarakat dalam mematuhi
protokol kesehatan. Hasil pada penelitian ini tidak dapat digeneralisasi dan hanya menunjukkan
hasil dari data responden yang diperoleh. Dengan demikian, peneliti menyarankan untuk
melakukan penelitian lebih lanjut menggunakan sampel yang representatif secara proporsi pada
setiap kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Hal ini disarankan agar data hasil penelitian dapat
membedakan responden tiap daerah zona infeksi COVID-19.
DAFTAR PUSTAKA
1. Wiersinga WJ, Rhodes A, Cheng AC, Peacock SJ, Prescott HC. Pathophysiology,
Transmission, Diagnosis, and Treatment of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A
Review. JAMA - J Am Med Assoc. 2020;2019.
2. Ong SWX, Tan YK, Chia PY, Lee TH, Ng OT, Wong MSY, et al. Air, Surface
Environmental, and Personal Protective Equipment Contamination by Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) from a Symptomatic Patient. JAMA -
J Am Med Assoc. 2020;323(16):1610–2.
3. Pandemi P, Kota C-DI, Larasati RA. https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jej/index ,.
2020;2(2):90–9.
4. Huckins JF, da Silva AW, Wang W, Hedlund E, Rogers C, Nepal SK, et al. Mental health
and behavior of college students during the early phases of the COVID-19 pandemic:
Longitudinal smartphone and ecological momentary assessment study. J Med Internet Res.
2020;22(6).
5. Knowledge, Attitudes and Practices of COVID‑19 Among Urban and rural.pdf.
6. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020
tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. 2020. p. 31–4.
7. Aldila N. 59 Negara Tutup Pintu untuk WNI, Begini Tanggapan Kemenlu [Internet]. 2020.
Available from: https://kabar24.bisnis.com/read/20200909/15/1289123/59-negara-tutup-
pintu-untuk-wni-begini-tanggapan-kemenlu
8. Pemprov Sumsel. Sumatera Selatan Tanggap COVID-19 [Internet]. 2020. Available from:
http://corona.sumselprov.go.id/index.php?module=home&id=1
9. Anum S. Minhas, M.D., Paul Scheel, M.D., Brian Garibaldi, M.D., Gigi Liu, M.D., M.Sc.,
Maureen Horton, M.D., Mark Jennings, M.D., M.H.S., Steven R. Jones, M.D., Erin D.
Michos, M.D., M.H.S., Allison G. Hays MD. Knowledge and Perceptions about COVID-19
among the Medical and Allied Health Science Students in India: An Online Cross-Sectional
Survey. Ann Oncol. 2020;(January):19–20.
10. Ammar A, Brach M, Trabelsi K, Chtourou H, Boukhris O. Effects of COVID-19 Home
Confinement on Eating Behaviour and Physical Activity : Results of the ECLB-COVID19
International Online Survey. 2020;(May).
11. Zhong BL, Luo W, Li HM, Zhang QQ, Liu XG, Li WT, et al. Knowledge, attitudes, and
practices towards COVID-19 among chinese residents during the rapid rise period of the
COVID-19 outbreak: A quick online cross-sectional survey. Int J Biol Sci.
2020;16(10):1745–52.
12. Vahia I V., Blazer DG, Smith GS, Karp JF, Steffens DC, Forester BP, et al. COVID-19,
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 297
Mental Health and Aging: A Need for New Knowledge to Bridge Science and Service. Am
J Geriatr Psychiatry. 2020;28(7):695–7.
13. Yang J, Zheng Y, Gou X, Pu K, Chen Z, Guo Q. Prevalence of comorbidities and its effects
in patients infected with SARS-CoV-2 : a systematic review and meta-analysis.
2020;(January).
14. Ayoub S, Al-khlaiwi T, Mahmood A, Sultan A. Biological and epidemiological trends in
the prevalence and mortality due to outbreaks of novel coronavirus COVID-19.
2020;(January).
15. Huang J, Liu F, Teng Z, Chen J, Zhao J, Wang X, et al. Public behavior change,
perceptions, depression, and anxiety in relation to the COVID-19 outbreak. Open Forum
Infect Dis. 2020;1–8.
16. Triyanto E, Kusumawardani LH. an Analysis of People ‘ S Behavioral Changes To Prevent
Covid -19 Transmission Based on Integrated Behavior Model. J Keperawatan Soedirman.
2020;15(2):66–73.
17. Cirrincione L, Plescia F, Ledda C, Rapisarda V, Martorana D, Moldovan RE, et al. COVID-
19 Pandemic: Prevention and protection measures to be adopted at the workplace. Sustain.
2020;12(9):1–18.
18. Azlan AA, Hamzah MR, Sern TJ, Ayub SH, Mohamad E. Public knowledge, attitudes and
practices towards COVID-19: A cross-sectional study in Malaysia. PLoS One [Internet].
2020;15(5):1–15. Available from: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0233668
19. Afzal et al. Community‑Based Assessment of Knowledge, Attitude, Practices and Risk
Factors Regarding COVID‑19 Among Pakistanis Residents.pdf.
20. Sajid M, Urooj A, Anam K, Waseem S, Hussain M, Yasmeen A, et al. Coronavirus disease
( COVID-19 ) and immunity booster green foods : A mini review. 2020;(April):3971–6.
21. González Maglio DH, Paz ML, Leoni J. Sunlight Effects on Immune System: Is There
Something Else in addition to UV-Induced Immunosuppression? Darvin ME, editor.
Biomed Res Int [Internet]. 2016;2016:1934518. Available from:
https://doi.org/10.1155/2016/1934518
22. Saragih, B. SF. GAMBARAN KEBIASAAN MAKAN MASYARAKAT PADA MASA
PANDEMI COVID-19.
23. Nandy S. Food for Urban Resilience in India. 2019;1–5.
24. Kathal R, Rawat P. Immunity Booster Herbs and their Conservation-A Review. 2016;135–
40.
25. Chandrasekara A, Shahidi F. Journal of Traditional and Complementary Medicine Herbal
beverages : Bioactive compounds and their role in disease risk reduction - A review. 2018;8.
26. Sekulic D, Blazevic M, Gilic B, Kvesic I, Zenic N. Prospective analysis of levels and
correlates of physical activity during COVID-19 pandemic and imposed rules of social
distancing; gender specific study among adolescents from Southern Croatia. Sustain.
2020;12(10):4–6.
27. Sari DK, Amelia R, Dharmajaya R, Sari LM, Fitri NK. Positive Correlation Between
General Public Knowledge and Attitudes Regarding COVID-19 Outbreak 1 Month After
First Cases Reported in Indonesia. J Community Health [Internet]. 2020;(0123456789).
Available from: https://doi.org/10.1007/s10900-020-00866-0
28. Wang Z, Yang H, Yang Y, Liu D, Li Z, Zhang X, et al. Prevalence of anxiety and
depression symptom , and the demands for psychological knowledge and interventions in
college students during COVID-19 epidemic : A large cross-sectional study.
2020;275(1023):188–93.
29. Cao W, Fang Z, Hou G, Han M, Xu X, Dong J. The psychological impact of the COVID-19
epidemic on college students in China. 2020;287(March):1–5.
30. Narayana G, Pradeepkumar B, Dasaratha J. Knowledge, perception, and practices towards
COVID-19 pandemic among general public of India: A cross-sectional online survey.
2020;(January).
31. Hager E, Odetokun IA, Bolarinwa O, Zainab A, Okechukwu O, Al-Mustapha AI.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 298
Knowledge, attitude, and perceptions towards the 2019 Coronavirus Pandemic: A bi-
national survey in Africa. PLoS One [Internet]. 2020;15(7 July):1–13. Available from:
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0236918
32. Taghrir MH, Borazjani R, Shiraly R. COVID-19 and iranian medical students; A survey on
their related-knowledge, preventive behaviors and risk perception. Arch Iran Med.
2020;23(4):249–54.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 299
MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL DIMASA
PANDEMI COVID-19 : TINJAUAN LITERATUR TERKINI
Ade Tyas Mayasari
*, Elsa Fitri Ana, Komalasari, Dessy Nur Safitri
Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu, Lampung
Corresponding email : [email protected]
ABSTRACT
Since December 2019, in Wuhan (Hubei Province, China), has successively found a new cases of infection
had never been detected before. This infection attacks the respiratory tract. The infection is called Covid-19
with the SARS-COv-2 virus as the main cause. After being first discovered in Wuhan, the Covid-19 outbreak
spread rapidly to other areas in China and around the world. Currently, there is an increase in new cases
globally as many as 1,844,959 million cases. Pregnant women are one of the groups susceptible to
transmission of the SARS-Cov-2 virus. Based on the cohort studies that have been conducted, viral infection
in pregnant women can cause complications for the mother and the fetus and can even lead to death in both.
We conducted a literacy study of health service management policies in pregnant women during the Covid-
19 pandemic from around the world published from February to September 2020. The literature we use is the
literature that has been published in the Pubmed and Sciencedirect databases. Management of maternal
health services in accordance with established health protocols can improve the quality of Maternal and
Child Health (MCH) services during the Covid-19 pandemic and support health service providers to
continue to pay attention to management of infection prevention and transmission. The availability of service
guidelines globally can help health workers prevent morbidity and mortality in mothers and babies related to
Covid-19.
Keyword : Health service management, Pregnant Women, Covid-19
ABSTRAK
Pada bulan Desember 2019, di Provinsi Wuhan-Hubei, China ditemukan kasus infeksi baru yang belum
pernah terdeteksi sebelumnya. Infeksi ini menyerang saluran pernafasan. Infeksi tersebut disebut dengan
Covid-19 dengan virus SARS-COv-2 sebagai penyebab utamanya. Setelah pertama kali ditemukan di
Wuhan, wabah Covid-19 menyebar dengan cepat ke daerah lain di China dan seluruh dunia. Saat ini secara
global terjadi peningkatan kasus baru sebanyak 1.844.959 juta kasus. Ibu hamil adalah salah satu kelompok
yang rentan terhadap penularan virus SARS-Cov-2. Berdasarkan studi kohort yang telah dilakukan, infeksi
virus pada ibu hamil dapat mengakibatkan komplikasi terhadap ibu dan janin bahkan dapat mengakibatkan
kematian pada keduanya. Kami melakukan studi literasi kebijakan manajemen pelayanan kesehatan pada ibu
hamil dimasa pandemi Covid-19 dari seluruh dunia yang dipublikasikan sejak Februari sampai September
2020. Literatur yang kami gunakan adalah literatur yang telah dipublikasikan di database Pubmed dan
Sciencedirect. Manajemen pelayanan kesehatan ibu sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan
dapat meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dimasa pandemi Covid-19 dan
mendukung penyedia layanan kesehatan untuk tetap memperhatikan manajemen pencegahan dan penularan
infeksi. Adanya panduan pelayanan secara global dapat membantu tenaga kesehatan dalam mencegah
kesakitan dan kematian pada ibu dan bayi terkait dengan Covid-19.
Kata Kunci: Manajemen pelayanan kesehatan, Ibu Hamil, Covid-19
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 300
PENDAHULUAN
Pada akhir bulan Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina ditemukan beberapa
kasus baru secara berturut-turut dengan gejala novel coronavirus pneumonia (NCP)3. Penyakit ini
disebabkan oleh infeksi virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2 )3.
Kasus pertama ditemukan di pasar ikan daerah kota Wuhan. Sejak tanggal 18-29 Desember 2019,
sebanyak lima pasien dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). Kemudian
pada tanggal 31 Desember 2019 hingga 03 Januari 2020 dilaporkan ada 44 kasus baru dengan
keluhan dan diagnosa yang sama. Dalam kurun waktu satu bulan, kasus ini meningkat dengan pesat
ke seluruh Cina bahkan sampai ke Negara Thailand, Jepang dan Korea Selatan13
. Karena
percepatan penyebaran penyakit ini sangat pesat, maka Pemerintah Republik Rakyat Tingkok
memasukkannya kedalam golongan penyakit menular kelas B. Selain itu, pencegahan dan
pengendalian penyakit menular serta tindakan pencegahan dan pengelolaan infeksi kelas A
dimasukkan kedalam Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok3. Pada tanggal 12 Januari 2020,
sebutan 2019 Novel Corona Virus (2019-nCoV) secara resmi ditetapkan oleh World Health
Organization (WHO)4. Seiring dengan berkembangnya penelitian yang dilakukan pada virus
jenis baru ini, pada tanggal 11 Februari 2020, WHO mengumumkan perubahan nama penyakit ini
yang telah menjadi wabah dunia, yaitu Coronavirus Disease-19 (COVID-19)13
. Penyakit ini terus
menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia sehingga pada tanggal 12
Maret 2020 WHO resmi mengumumkan bahwa COVID-19 sebagai pandemik.
Lembaga kesehatan dunia atau WHO melaporkan terlah terjadi lebih dari 32,7 juta kasus
COVID-19 di seluruh dunia. Pada tanggal 21 sampai dengan 27 September 2020 terdapat kurang
lebih 2 juta kasus baru dan 36.000 kematian baru. Peningkatan kasus terbesar dalam kurun waktu
antara 21-27 September 2020 terjadi di wilayah Amerika dengan presentase peningkatan kasus
baru sebanyak 38% dan kasus kematian baru sebanyak 52%. Negara-negara di wilayah Mediterania
Timur melaporkan peningkatan kasus sebanyak 9% jika dibandingkan dengan kasus pada minggu
sebelumnya. Wilayah Eropa melaporkan peningkatan kematian yang subtansial sebanyak 9%.
Sedangkan Negara-negara di wilyah Afrika, Pasifik Barat dan Asia Tenggara melaporkan adanya
penurunan kasus baru dan kematian yang terjadi dalam satu minggu ini. Meskipun WHO
melaporkan bahwa Wilayah Asia Tenggara mengalami penurunan kasus baru dan kematian baru,
namun Indonesia terus mengalami peningkatan kasus COVID-19 ini. Dari tanggal 01 Oktober
hingga 02 Oktober 2020, terjadi peningkatan kasus baru sebanyak 4.317 kasus dan kasus kematian
baru meningkat sebanyak 116 kasus, namun peningkatan kasus dan kematian baru tersebut diiringi
pula kasus pasien yang sembuh yaitu sebanyak 2.853. Jumlah kasus di Indonesia pada tanggal 02
Oktober 2020 yaitu, positif COVID-19 sebanyak 295.499, pasien sembuh (positif COVID-19)
sebanyak 221.340, dan pasien meninggal (positif COVID-19) sebanyak 10.972.
COVID-19 awalnya adalah infeksi yang penularannya terjadi dari hewan vertebrata ke
manusia (zoonosis). Selanjutnya virus ini berkembang melalui transmisi dari manusia ke manusia
lainnya melalui percikam cairan sekresi dari saluran pernafasan orang yang terinfeksi1. COVID-19
adalah penyakit yang menyerang saluran pernafasan yang kemudian bermanifestasi dengan gejala
demam, batuk, kelelahan, hidung tersumbat dan sesak nafas, batuk kering, sakit kepala, diare 7,3,1.
Namun 23% orang yang telah terinfeksi menunjukkan kondisi tanpa gejala. Komplikasi yang tejadi
dari infeksi ini adalah adanya pneumonia berat, sindrom pernafasan akut, kelainan jantung, sepsis
dan syok septik1. Masa inkubasi dari virus ini adalah sekita 4 sampai dengan 6 hari dan dapat
bervariasi antara 2 sampai dengan 14 hari1.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 301
Data mengenai peningkatan kasus COVID-19 ini telah dilaporkan secara nasional maupun
secara global, namun hingga saat ini belum ada data spesifik mengenai jumlah ibu hamil yang
terpapar virus COVID-19 di Indonesia. Meskipun demikian, jika dilihat, dari wabah yang pernah
terjadi sebelumnya di daerah Timur Tengah pada tahun 2012 yang disebabkan oleh keluarga virus
yang sama dengan COVID-19 yaitu Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)
menunjukkan bahwa lebih dari 10.000 pasien di seluruh dunia terinfeksi MERS-CoV ini. Dari
jumlah tersebut, sebanyak 25% menginfeksi wanita hamil4. Hal tersebut karena wanita hamil lebih
rentan terhadap penularan infeksi yang dapat mengakibatkan komplikasi. Faktanya, seorang wanita
hamil akan mengalami perubahan yang fisiologis pada sistem kardiovaskuler, pernafasan dan
sistem koagulasi yang dapat menyebabkan meningkatnya risiko morbiditas dan mortalitas1. Selain
dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas pada ibu hamil, COVID-19 juga dapat berdampak
terjadinya komplikasi pada janin, diantaranya adalah, keguguran, Pertumbuhan Janin Terhambat
(PJT) atau Intra Uterine Growth Restriction (IUGR) dan kelahiran prematur, kelainan pada saraf
dan kematian pada bayi baru lahir2.
METODE
Studi yang kami lakukan menggunakan metodologi tinjauan literatur terkini. Metode yang
digunakan adalah dengan melakukan studi literasi tentang kebijakan manajemen pelayanan
kesehatan pada ibu hamil dimasa pandemi Covid-19 dari seluruh dunia yang dipublikasikan sejak
bulan Februari sampai September 2020. Databased yang kami gunakan adalah Pubmed dan
Sciencedirect. Kata kunci yang kami gunakan adalah ―pregnancy management AND covid-19‖.
HASIL PENELITIAN
1. GEJALA COVID-19
Sebagian besar pasien pada awal terinfeksi memiliki gejala yang ringan dan sekitar 20%
mengalami gejala yang berat1. Secara umum, ibu hamil lebih berisiko mengalami morbiditas dan
mortalitas dari terjadinya infeksi saluran pernafasan tertentu, seperti pada kasus infeksi virus H1N1
dan varicella pneumonia. Oleh karena itu, ibu hamil yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 juga dapat
berisiko mengalami gangguan saluran pernafasan yang dapat mengganggu kondisi ibu dan janin
yang dikandungnya. Sama seperti pasien umum yang didiagnosis COVID-19, ibu hamil juga
mengalami gejala yang sering ditemukan yaitu : demam, batuk dan flu serta sesak nafas. Kondisi
sesak nafas pada ibu hamil lebih sulit ditegakkan diagnosis nya jika tidak dilakukan pemeriksaan
secara menyeluruh karena secara fisiologis, ibu hamil mengalami peningkatan kebutuhan oksigen
untuk metabolisme ibu dan janinnya. Kurang lebih 80% Ibu hamil yang mengalami COVID-19
menunjukkan gejala ringan, 15% mengalami gejala berat dan 5% mengalami kondisi kritis13
.
Gambaran umum dari gejala yang sering dialami oleh wanita hamil dengan COVID-19 dapat
dilihat dari tabel 1 berikut ini :
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 302
Tabel 1. Gambaran umum dari gejala yang sering dialami oleh wanita hamil dengan
COVID-19
Gejala
Lopez et al. 1 Dashraath et
al. 2
Elshafeey et al.
17
Chen et al. 16 Yu et al. 15
% % % % % Demam 80-100 84 67.3 75 86
Batuk 59-82 28 65.7 73 14
Sesak Nafas 31-54 18 7.3 7 14
Sakit Kepala 6-17 Kelelahan 44-70
Diare 2-10 7.3 7 14
Seorang ibu hamil akan mengalami perubahan secara fisiologis pada sistem kardiovaskuler,
pernafasan dan sistem koagulasi sehingga komplikasi akibat COVID-19 pada ibu hamil harus
diidentifikasi dan ditangani sejak dini1.
2. Komplikasi Pada Janin Dengan Ibu Positif COVID-19
Terjadinya demam selama masa kehamilan dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada
saraf janin. Komplikasi lainnya yang dapat terjadi pada bayi dengan ibu positif COVID-19 adalah
keguguran atau abortus, timbulnya kecacatan, persalinan prematur, Intra Uterine Growth
Restriction (IUGR) atau Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT)1. Dari beberapa komplikasi yang
dapat terjadi pada janin tersebut, kelahiran prematur adalah komplikasi yang sering terjadi yaitu
sebanyak 41-47%. Namun hingga saat ini, belum ada cukup bukti untuk menentukan hubungan
antara COVID-19 dan persalinan prematur, meskipun pada beberapa kasus ibu hamil dengan
COVID-19 terjadi ruptur membran13
. Studi pada ibu hamil dengan positif COVID-19 belum
menunjukkan bahwa COVID-19 bersifat teratogenik. Sebuah studi lapangan menunjukkan bahwa
telah terjadi kegugran pada usia kehamilan 19 minggu yang menggambarkan adanya insufisiensi
akut pada plasenta yang mengakibatkan terjadinya keguguran. Kasus tersebut didukung oleh
adanya virus pada plasenta, namun belum ada bukti konkreat adanya transmisi secara vertikal
antara ibu dan janin yang dikandungnya sehingga masih diperlukan adanya penelitian lebih lanjut
untuk menyelidiki hubungan potensial tersebut. Tidak hanya itu, potensial terjadinya pertumbuhan
janin terhambat dan komplikasi lainnya pada janin dengan ibu hamil positif COVID-19 juga belum
dapat ditentukan dengan pasti dan masih memerlukan data penelitian lebih lanjut13
.
3. Penularan Penyakit
SARS-CoV-2 adalah virus RNA sense positif yang tidak tersegmentasi. Virus ini adalah
virus dalam kelompok keluarga virus corona (CoV). Keluarga virus corna terdiri dari empat virus
yang dua diantaranya dapat menyebabkan terjadinya flu. Dua virus tersebut adalah Severe Acute
Respratory Syndrome (SARS) CoV, Middle East Respiratory syndrome (MERS) CoV. SARS-
CoV dan MERS-CoV telah menyebabkan epidemi dan mengakibatkan borbiditas dan mortalitas
yang tinggi, terutama pada ibu hamil6. COVID-19 adalah infeksi yang disebabkan oleh virus
SARS-CoV-2, virus ini awalnya adalah virus yang bersifat zoonosis atau infeksi yang menular dari
hewan ke manusia. Transmisi virus SARS-CoV-2 kemudian berkembang dari satu orang ke orang
lain melalui tetesan udara dari hasil pernafasan2. Penelitian yang dilakukan sejauh ini menunjukkan
bahwa penularan COVID-19 melalui tiga mekanisme, yaitu tetesan udara, kontak langsung dari
orang ke orang lainnya dan kontak dengan fomites7. Tetesan udara dari orang yang terinfeksi dalam
jarak < 2 meter atau adanya kontak langsung dengan orang yang terinfeksi dapat membangun mata
rantai penularan virus ini. Hingga saat ini belum ada bukti bahwa virus juga dapat berkembang
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 303
dalam cairan genital, urin, cairan ketuban, darah pada tali pusat dan Air Susu Ibu (ASI)1. Namun
ada risiko transmisi atau penularan secara vertikal jika dilihat dari jenis virus yang serupa dengan
SARS. Mayoritas ibu hamil yang tertular COVID-19 adalah pada trimester tiga kehamilan2.
4. Manajemen Ibu Hamil dengan COVID-19
Tujuan pengelolaan pelayanan COVID-19 oleh WHO adalah :
a. Mengidentifikasi, perbaikan jalan nafas, isolasi dan perawatan lebih awal pada bayi baru
lahir yang terpapar COVID-19 dan mengoptimalkan perawatan untuk pasien yang telah
dinyatakan terinfeksi.
b. Mencegah penularan dari satu orang ke orang lainnya untuk mengurangi infeksi sekunder
dan kontak dengan petugas kesehatan
c. Membangun dan memelihara ikatan antara ibu dan bayinya dengan sebaik mungkin.
Berikut ini adalah pedomam umum dalam pelayanan kebidanan untuk mengurangi risiko
penularan COVID-19 :
a. Mengurangi kunjungan ANC dan memfokuskan kunjungan ANC pada empat kali kunjungan
yaitu pada usia kehamilan < 16, 28, 32 dan 38 minggu dan memodfikasi jadwal kunjungan
pada usia kehamilan > 36 minggu dengan menggunakan pelayanan online, hal ini bertujuan
untuk meminimalkan trejadinya risiko infeksi
b. Menghindari pemeriksaan ANC dari keramaian sehingga perlu diatur jadwal untuk setiap
pasien
c. Selama proses konsultasi, petugas kesehatan harus menjaga jarak aman dari pasien
d. Menerapkan kewaspadaan universal untuk semua penyakit menular
e. Sebelum dan setelah proses konsultasi, tenaga kesehatan harus mencuci tangan dengan
menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan
f. Saat dilakukan skrining pada kunjungan ANC, harus ditanyakan riwayat perjalanan dalam
beberapa hari sebelumnya, apakah pernah melakukan perjalanan dari daerah berisiko tinggi.
Selain itu apakah ibu memiliki gejala demam, batuk dan sesak nafas. Apabila ditemukan factor
risiko tersebut maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut di area yang terpisah dari pasien yang
lainnya
g. Konsultasi melalui telfon harus direncanakan untuk kondisi non daruratan dengan tujuan untuk
mengurangi kunjungan ke klinik atau rumah sakit
h. Pasien dengan keluhan dan kondisi serius harus dikategorikan kedalam kondisi darurat tanpa
mempertimbangkan usia kehamilan dan status pemeriksaan dengan tujuan agar ia mendapat
prioritas pelayanan dengan tepat
i. Tindakan operasi SC disarankan dengan penanganan anastesi dan neurologi yang tepat
Ibu hamil dianjurkan untuk menerapkan jarak sosial atau social distancing dan mengikuti
panduan isolasi diri untuk mencegah terpaparnya COVID-19. Selain itu, selalu menjaga kebersihan
tangan dengan cara rajin mencuci tangan juga direkomendasikan13
. Ibu hamil yang memiliki gejala
akan dinilai sebagai suspect sampai didapatkan hasil pemeriksaan klinis secara menyeluruh. Hal ini
dilakukan untuk menciptakan management isolasi dan pengobatan yang kondusif secara dini3.
Apabila ditemukan salah satu keluhan dan sejarah epidemiologi penularan serta adanya manifestasi
pemeriksaan klinis maka tindakan yang harus dilakukan adalah :
Historikal epidemiologi3 :
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 304
1. Riwayat perjalanan atau tempat tingga di daerah yang ada kasus positif COVID-19 atau
berkumpul dengan komunitas yang didalamnya ada kasus positif COVID-19 pada 14 hari
sebelum timbulnya gejala infeksi
2. Riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi terinfeksi SARS-CoV-2 dalam waktu 14 hari
sebelumnya
3. Riwayat kontak dengan pasien yang mengalami demam atau gejala gangguan pernafasan dalam
waktu 14 hari sebelumnya
4. Adanya clustering positif COVID-19 ditempat ia berada
Manifestasi Klinis3,1
:
1. Demam persistem > 380C meskipun sudah diobati menggunakan paracetamol
2. Adanya gejala gangguan pernafasan
3. Adanya pengurangan jumlah total leukosit dan limfosit
4. Pada foto rontgen menunjukka adanya pneumonia
5. Wanita hamil dengan penyakit penyerta lainnya seperti hipertensi kronis, penyakit paru-paru,
diabetes sebelum kehamilan, imunosupresi, penerima transplantasi organ, terinfeksi HIV dengan
<350 sel CD4 +, pasien yang menerima kortikosteroid
6. Penilaian keparahan dengan skala CURB, yaitu :
a. Confusion (Acute) atau kecemasan yag berlebihan
b. Urea > 19 mg/dL atau kandungan urea dalam urin > 19 mg/dL
c. Respiratory : ≥ 30 bpm atau pernafasan ≥30 kali per menit
d. Blood Pressure Systolic ≤ 90 or diatolic ≤ 60 mmHg atau tekanan darah sistolik ≤ 90 dan
diastole ≤ 60 mmHg
Selama masa pandemi, prinsip umum yang diterapkan pada pelayanan antenatal care (ANC)
adalah dengan meminimalkan kunjungan langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Konsultasi via
telfon dan video call merupakan salah satu cara efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Ibu
hamil dengan gejala COVID-19 harus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan jika
memungkinan, jadwal kunjungan ANC ditunda serta harus menjalani karantina mandiri. Apabila
gejala masih berlanjut, maka ibu harus mengkonfirmasi ke tenaga kesehatan untuk di tes dan/atau
dirawat inap sesuai dengan protap penanganan COVID-19. Ibu hamil yang sebelumnya
terkonfirmasi COVID-19 dan telah dinyatakan sembuh dari infeksi virus SARS-CoV-2, tetap harus
dilakukan pemantauan secara teratur dan penilaian kondisi perkembangan serta kesejahteraan
janin.13
Berikut ini adalah beberapa pedoman umum dalam pengelolaan pelayanan ANC untuk
mengurangi risiko penularan/paparan COVID-19.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 305
Gambar 1 Rangkuman manajemen penanganan COVID-19 selama kehamilan
Lopez et al. Coronavirus Disease 2019 in Pregnancy: A Clinical Management Protocol and
Considerations for Practice. S. Karger AG 2020
Adanya demam yang menetap (> 380C) meskipun sudah diberikan paracetamol
Pada foto rontgen terdapat kriteria pneumonia
Adanya penyakit penyerta seperti : hipertensi kronik, diabetes sebelum kehamilan,
penyakit paru-paru, insufisiensi ginjal dan immunosuppression
Adanya skor CURB > 0 :
Confusion (Acute)
Urea > 19 mg/dL
Respiratory : ≥ 30 bpm
Blood Pressure Systolic ≤ 90 or diatolic ≤ 60 mmHg
Tidak ada Ada
Perawatan di Rumah Sakit Isolasi mandiri di rumah
Pemenuhan hidrasi
Pemberian antivirus : lopinavir/ritonavir
dalam 7-14 hari (Penggunaan harus
diawasi secara ketat)
Hydroxychloroqiune dalam 4 hari
(Penggunaan harus diawasi secara ketat)
Azitromisin dalam 4 hari
Low Molecular Weight Heparin
(LMWH) profilaksis (diberikan sampai
dengan 2 minggu setelah perawatan)
Jika alveolar mengecil dan prokalsitonin
meningkat, pertimbangkan pemberian
ceftriaxone + teicoplanin
Pertahankan SO2 > 94%
Pemantauan detak jantung janin (CTG
jika > 28 minggu)
Pertimbangkan persalinan jika usia
kehamilan antara 32-34 minggu
Pemenuhan hidrasi
Jika diperlukan, minum
paracetamol dengan dosis
maksimal 4 gram per hari
Pemantauan melalui telfon dalam
24 jam, 48 jam dan 7 hari
Penundaan kunjungan rutin secara
langsung dalam waktu 4 minggu
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 306
Jika ditemukan salah satu dari manifestasi gejala klinik, maka segera lakukan penanganan
pada kasus infeksi ringan dengan cara melalukan isolasi mandiri di rumah. Selama melakukan
isolasi tersebut harus dilakukan tindakan :
a. Hidrasi
b. Mengontrol suhu 2 kali sehari
c. Jika diperlukan, minum paracetamol 500 – 1.000 mg dalam jangka waktu 6-8 jam
d. Memberikan kabar atau pemantauan melalui telefon dalam 24 jam, 48 jam hingga 7 hari
e. Penundaan kunjungan rutin secara langsung dalam waktu 4 minggu
f. Melakukan aktivitas fisik ringan dan menghindari bed rest yang terlalu lama untuk mencegah
risiko terjadinya thrombosis.
Pada kasus tingkat sedang hingga berat, pelayanan yang harus diterapkan adalah sebagai
berikut :
1. Dilakukan perawatan di Rumah Sakit pada unit isolasi dengan pemantauan rutin tanda-tanda
vital yang meliputi tekanan darah, detak jantung, frekuensi pernafasan dan SO2
2. Meskipun belum ada bukti dari uji coba klinis yang dapat digunakan, namun pengobatan
farmakologis dibutuhkan untuk mengurangi gejala COVID-19. Pengobatan farmakologis
tersebut yaitu :
a. Lopinavir/ritonavir (100 mg/25 mg) 2 tablet setiap 12 hari (7-14 hari tergantung pada
evolusi kondsi klinis)
b. Hydroxychloroquine sulphate 400 mg setiap 12 jam di hari pertama kemudian dilanjutkan
dengan dosis 200 mg setiap 12 jam dalam 4 hari
c. Azitromisin 500 mg pada dosis pertama kemudian dilanjutkan dengan dosis 250 mg setiap
24 jam sampai dengan 4 hari yang diberikan secara oral atau intravena.
Perawatan farmakologis ini memiliki kontraindikasi dalam kehamilan, namun perlu
persetujuan dan pemantuan secara ketat dalam penggunaanya.
a. Dalam kasus infiltrate alveolar dan/atau prokalsitonin meningkat (dalam dugaan adanya
peningkatan infeksi bakteri), pemberian ceftriaxone 1-2 gram per 24 jam secara intravena +
teicoplanin 400 mg setiap 12 jam untuk 3 kali pemberian kemudian dilanjutkan dengan 400 mg
setiap 24 jam
b. Pemberian methyiprednisolone (untuk pengelolaan sindrom gangguan pernafasan akut),
Tocilizumab (sebagai anti inflamasi nonoklonal antibody dengan efek penghambatan IL-6) atau
Remdesivir (sebagai penghambat RNA polymerase dengan aktivitas in vitro dalam melawan
SARS-CoV-2). Namun pemberian obat golongan ini masih terus diteliti keamanannya bagi ibu
hamil
Pemantauan kesejahteraan janin dengan menggunakan Cardiotocography (CTG) secara rutin
dan tergantung pada usia kehamilan dan kondisi ibu1.
Gambar 2.
Skema kontinuitas pelayanan dan pengendalian infeksi di tiap unit kerja kebidanan
Tujuan : Menjamin kontinuitas pelayanan, jarak sosial petugas kesehatan dan pengendalian infeksi
Tenaga Kesehatan yang tergabung dalam satu tim dapat terdiri dari resident, perawat dan tenaga
medis lainnya, misalnya sonographer. Waktu kerja dalam satu shift adalah 12 jam dan dilaksanakan
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 307
salam satu minggu, kecuali hari libur yang telah ditentukan. Tenaga kesehatan juga harus
memastikan waktu istirahat yang cukup.
× ×
Tim Rawat Jalan :
Tempat pelayanan rawat
jalan meliputi :
1. Klinik kehamilan
2. Klinik Spesialis ibu
dan anak
3. Klinik USG
Hal-hal yang harus
dilakukan pada setiap
kunjungan :
Pemeriksaan suhu
secara rutin
Memetakan pasien
berdasarkan zonasi
wilayah terpapar
COVID-19
Jika memungkinkan,
menunda
pemeriksaan USG
Jika memungkinkan,
perimbangkan untuk
menunda layanan
ART
Memfasilitasi
pelacakan interaksi
yang telah dilakukan
sebelumnya jika
pasien dinyatakan
positif COVID-19
Tetap memberikan
pelayanan kesehatan
reproduksi
Tim Rawat Inap :
Tempat pelayanan rawat
jalan adalah Rumah
Sakit dengan pelayanan :
1. Menerima perawatan
pasien antenatal
2. Menerima perawatan
pasien postnatal
3. Menerima perawatan
pasien rujukan
(termasuk pasien
dengan kasus-kasus
infeksi)
Pelayanan yang harus
diberikan pada unit
rawat inap adalah :
Perawatan Enhanced
Recovery After
Surgery (ERAS)
sesuai dengan
protocol kesehatan
yang berlaku
Pemberian obat-
obatan yang masih
terbungkus dalam
kemasannya
Pemulihan setelah
operasi
Tim Penanganan
Kelahiran :
Tempat pelayanan rawat
jalan adalah Rumah
Sakit dengan pelayanan :
1. Pelayanan persalinan
2. Pelayanan operasi
SC elektif dan
darurat
Hal-hal yang harus
dilakukan pada unit
penanganan kelahiran
adalah :
Pemeriksan suhu
rutin
Menggunakan Alat
Perlindungan Diri
(APD) berdasarkan
profil risiko infeksi
Persalinan SC untuk
meminimalkan risiko
komplikasi
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 308
Note : × Meminimalkan kontak fisik antar tim untuk mengurangi risiko infeksi silang
Dashraath. COVID-19 pandemic and pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2020.
Dalam masa pandemi, menjaga jarak sosial telah terbukti efektif untuk mencegah penularan
COVID-19. Pemberian pelayanan kebidanan dapat diterapkan dengan skema ini. Dalam
memberikan pelayanan, harus memperhatikan prinsip pencegahan infeksi dengan memakai Alat
Perlindungan Diri (APD) sesuai tingkat level infeksi. Jika salah satu dari anggota tim dinyatakan
terinfeksi COVID-19, maka ia harus dikarantina selama 2 minggu2.
Selain menerapkan pembagian tim dalam pelayanan, pemeriksaan kehamilan dilaksanakan
sesuai dengan pedoman perawatan kesehatan berdasarkan perjanjian antara ibu hamil dan tenaga
kesehatan. Ibu hamil juga harus memperhatikan pergerakan janin nya terutama dalam usia
kehamilan trimester tiga. Apabila ada ibu hamil yang dicurigai terdiagnosis COVID-19 maka ia
harus menjalani pemeriksaan menyeluruh di Rumah Sakit rujukan yang telah ditentukan.
Pemantauan detak jantung janin dan pemeriksaan USG dilakukan untuk menilai kondisi dan
kesejahteraan janin di dalam kandungan. Untuk meminimalkan terjadinya penularan virus dan
infeksi silang, pemeriksaan kehamilan disarankan melalui konsultasi online untuk memberikan
asuhan pada ibu hamil3.
Ibu hamil yang memiliki gejala klinis mengarah pada COVID-19 harus segera diisolasi
dalam ruangan tersendiri. Kasus yang telah dinyatakan positif harus dirawat dalam ruangan tertutup
dan diminimalkan untuk berinteraksi dengan orang lain. Ibu hamil dengan gejala dan kondisi kritis
harus dirawat di unit perawatan intensif. Rumah sakit juga harus menyediakan ruangan bersalin
tersendiri untuk proses operasi SC bagi ibu hamil yang terkonfirmasi positif COVID-19. Selain itu,
ruang perawatan untuk isolasi bayi yang dilahirkan dari ibu yang positif juga harus dibedakan.
Idealnya, ruangan antara ruang operasi dan ruang bayi letak nya berdekatan satu sama lain untuk
membatasi wilayah pergerakan tenga medis yang menanganinya. Pengunjung pasien juga harus
dibatasi dan interaksi antara pasien dengan keluarganya dapat melalui jendela tertutup4. Berikut ini
adalah diagram alur konsultasi ibu hamil dengan suspected infeksi COVID-19 :
Gambar 3. Alur konsultasi ibu hamil dengan suspected infeksi COVID-19
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 309
Chen et al. Expert consensus for managing pregnant women and neonates born to mothers
with suspected or confirmed novel coronavirus (COVID-19) infection. Int. Journal of
Gynecology Obstetric. 2020
Ibu hamil dan bayi baru lahir dengn gejala COVID-19 harus dirujuk ke Rumah Sakit rujukan
yang telah ditentukan
Suspected COVID-19
Direkomendasikan menjalani isolasi di ruang khusus yang tertutup
Memeriksa etiologi penularan infeksi secara lengkap
Setelah dilakukan dua kali tes
patogenik didapatkan hasil tes
negative (waktu pengambilan
sampel minimal berjarak 1 hari)
Dikecualikan dari kasus
infeksi COVID-19
Penghentian isolasi dan
pemeriksaan rutin
antenatal di klinik
kebidanan
Jika dilakukan test
dengan hasil positif
Terkonfirmasi positif
COVID-19
Direkomendasikan untuk
menjalani isolasi pada
ruang khusus untuk
dilakukan pemeriksaan
ANC secara rutin dan
proses persalinan
Apabila kondisi pasien
kritis, maka perawatan
dipindahkan ke ruang
ICU khusus isolasi pasien
COVID-19
Tim medis dari multidisiplin merencanakan terminasi
kehamilan, metode persalinan dan metode anastesi
Penyembuhan dari
COVID-19
Bayi baru lahir harus
diisolasi selama 14 hari dan
harus dipantau secara ketat,
tidak dierkomendasikan
untuk menyusu langsung
pada ibu selama isolasi
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 310
COVID-19 ditularkan melalui infeksi droplet dan kontak terhadap permukaan (face-to-
fomite), penularan juga dapat melalui udara. Persistensi virus dapat hidup dipermukaan sampai
empat hari. Orang tanpa gejala juga dapat menularkan penyakit ini, sehingga penggunaan masker
ketika keluar rumah sangat disarankan untuk memutus mata rantai penularan. Berikut ini adalah
pedoman untuk mempertimbangkan kerentanan ibu hamil terhadap COVID-196:
Pedoman 1 : Setiap ibu hamil dianggap sebagai kelompok berisiko tinggi karena
adanya perubahan respon imun. Ibu hamil yang terinfeksi akan mengalami kondisi lebih
berat dan membutuhkan perawatan yang lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tidak
hamil. Oleh karena itu, semua ibu hamil harus selalu melakukan tindakan pencegahan secara
rutin dengan cara menjaga kebersihan tangan dan mendisinfeksi dengan etanol >60% serta
menjaga jarak social, termasuk dengan pasangannya
Pedoman 2 : Bagi ibu hamil yang bekerja di lingkunan dengan risiko tinggi (missal
ruang persalinan, operasi, bangsal perawatan khusus pernafasan dan unit perawatan intensif)
sebaiknya dipindahkan ke lingkungan kerja dengan risiko rendah.
Pedoman 3 : Sampai saat ini, ibu hamil mengalami gejala perjalanan penyakit yang
hampir sama dengan masyarakat umum. Namun pada wabah sebelumnya yang hampir serupa
dengan virus ini, ibu hamil tidak hanya lebih rentan tetapi juga mengalami gejala yang lebih
parah. Manajemen perawatan pada ibu hamil akan lebih sulit dan intensif, sehingga ibu hamil
dengan usia kehamilan lebih dari 24 minggu harus dipantau secara intensif, bahkan
disarankan untuk ibu hamil diberhentikan dari tempat kerja yang berisiko tinggi.
Pedoman 4 : Komplikasi potensial yang dapat terjadi pada ibu hamil dengan COVID-
19 adalah kelahiran prematur, premature rupture of membranes (PPROM) dan gawat janin,
hal ini karena ibu hamil mengalami hipoksemia. Persalinan dengan operasi SC lebih
disarankan demi mengurangi risiko
Pedoman 5 : Waktu persalinan harus segera ditentukan oleh tim medis multidisiplin
berdasarkan tingkat keparahan dan kondisi klinis ibu dan janinnya. Manajemen perawatan
intensif ibu hamil pada usia kehamilan > 24 minggu harus lebih intensif seperti manajemen
pernafasan, pemantauan janin dan pemantauan lainnya
Pedoman 6 : Terjadinya pertumbuhan janin terhambat menjadi salah satu komplikasi
potensial jangka panjang setelah pasien pulih dari COVID-19. Oleh karena itu, pertumbuhan
janin harus dipantau secara intensif melalui pemeriksaan USG pada usia kehamilan 24-28-
32-36 minggu. Selain itu, pengukuran kecukupan cairan ketuban juga harus dipantau.
Pedoman 7 : Sejauh ini belum ditemukan adanya penularan secara vertikal antara ibu
dan janinnya pada usia kehamilan 25 hingga 39 minggu. Begitupun komplikasi yang dapat
terjadi pada trimester pertama.
Pedoman 8 : Penularan vertikal melalui jalan lahir mungkin tidak terjadi. Oleh karena
itu, pemantauan kondisi ibu dan janin harus dipastikan dalam kondisi stabil.
KESIMPULAN DAN SARAN
1. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-Cov-2 yang dapat
ditularkan dari satu orang ke orang lainnya. Penyakit ini menyerang saluran pernafasan melalui
tetesan atau percikan air setelah kontak dengan orang terinfeksi pada jarak < 2 meter atau
adanya kontak langsung dengan permukaan yang terkontaminasi
2. Sebagian besar pasien memiliki gejala ringan
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 311
3. Ibu hamil adalah kelompok yang rentan terhadap infeksi virus dan penyakit menular lainnya
karena adanya perubahan fisiologis dan fungsi imunologi sehingga pemantauan kesehatan ibu
dan janin harus dijaga dan dipantau. Pencegahan dan pemantauan tersebut dilakukan dengan
tindakan pencegahan khusus untuk meminimalkan infeksi silang antara petugas kesehatan dan
pasien
4. Manajemen kebidanan pada ibu hamil didasarkan pada rekomendasi praktik terbaik. Terapi
antivirus dan penggunaan kortikosteroid dapat diberikan untuk meringankan gejala
5. Manajemen pelayanan kesehatan ibu sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan
dapat meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dimasa pandemi
Covid-19 dan mendukung penyedia layanan kesehatan untuk tetap memperhatikan manajemen
pencegahan dan penularan infeksi.
6. Adanya panduan pelayanan secara global dapat membantu tenaga kesehatan dalam mencegah
kesakitan dan kematian pada ibu dan bayi terkait dengan COVID-19.
DAFTAR PUSTAKA
1. Lopez Marta., Gonce Anna., Meler Eva., Plaza Ana., Hernandez Sandra et al. 2020.
Coronavirus Disease 2019 in Pregnancy: A Clinical Management Protocol and Considerations
for Practice. S.Karger, Basel. Doi : DOI: 10.1159/000508487
2. Dashraath Pradip et al. 2020. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic and
Pregnancy. Am J Obstet Gynecol. Doi : 10.1016/j.ajog.2020.03.021
3. WANG Shao-Shuai et al. 2020. Experience of Clinical Management for Pregnant Women and
Newborns with Novel Coronavirus Pneumonia in Tongji Hospital, China. Current Medical
Science. Doi : https://doi.org/10.1007/s11596-020-2174-4
4. Chen Dunjin et al. 2020. Expert consensus for managing pregnant women and neonates born to
mothers with suspected or confirmed novel coronavirus (COVID-19) infection. . Int. Journal of
Gynecology Obstetric. Doi : 10.1002/ijgo.13146
5. Donders Francesca et al. 2020. ISIDOG Recommendations Concering COVID-19 and
Pregnancy. Diagnostics. Doi : 10.3390/diagnostics10040243
6. Ezenwa B.N et al. 2020. Management of covid-19: a practical guideline for maternal and
newborn health care providers in Sub-Saharan Africa. The Journal of Maternal-fetal &
Neonatal Medicine. Doi : 10.1080/14767058.2020.1763948
7. Lou Yongwen. Yin Kai. 2020. Management of Pregnant Women Infected with a COVID-19.
The Lancet. Doi : https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30191-2
8. Abourida Yassamine et al. 2020. Management of Severe COVID-19 in Pregnancy. Case
Report Obstetrics and Gynecology. Doi : https://doi.org/10.1155/2020/8852816
9. Mei Youwen et al. 2020. Obstetric Management of COVID-19 in Pregnant Women. Frontiers
in Microbiology. Doi : 10.3389/fmicb.2020.01186
10. Susilo Adityo dkk. 2020. Coronavirus Disease 2019. Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal
Penyakit Dalam Indonesia Vol.7, No.1.
11. Ryan A. Gillian et al. 2020. Clinical Update on COVID-19 in Pregnancy :A Review Article. J.
Obstet. Gynecol. Res. Doi : 10.1111/jog.14321
12. Wu Xiaoqing et al. 2020. Radiological Findings and Clinical Characteristics of Pregnant
Women with COVID-19 Pneumonia. Int. Journal of Gynecology Obstetrics. Doi :
10.1002/ijgo.13165
13. Omer Sumaira et al. 2020. Preventive Measures and Management of COVID-19 in Pregnancy.
Grugs & Therapy Perspective. Doi : https://doi.org/10.1007/s40267-020-00725-x
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 312
DETERMINAN KELUHAN MATA PADA PEKERJA
DI DEPOT PASIR KOTA PALEMBANG
Dini Arista Putri,
1 Amrina Rosyada,
2 Desri Maulina Sari
3
1 Bagian Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya
2Bagian Biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya
3Bagian Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya
Jl. Palembang Prabumulih KM. 32, Indralaya Indah Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan
Corresponding email : [email protected]
DETERMINAT OF EYESTRAIN SYMPTOM ON WORKS IN
THE DEPOT SAND IN PALEMBANG CITY
ABSTRACT
The work area of the sand depot contains various potential hazards that can affect the health of workers or
can cause disease. One of the polluting factors in the workplace is dust. Dust is solid particles caused by
natural or mechanical forces from organic and inorganic materials. Dust can irritate the eyes, namely Total
Dust and PM10. Palembang City is a city flowed by the Musi River. The Musi River, the Musi River are also
a sand mining site for development in Palembang City. Several miners carry out their activities which are
then taken to sand depots on the banks of the Musi River, so that workers are likely to be directly exposed to
dust. The number of respondents was 74 people and the data were processed by univariate and bivariate
analysis. Based on the results of the study, the variables related to smoking (Pavlue = 0.002) and body mass
index (Pavlue = 0.002) with eye complaints. The characteristics of the respondent influence the occurrence of
eye complaints so that the respondent should adjust their diet and reduce smoking, especially when working.
Keywords: Dust, Depot Sand, Symptom of Eyestrain
ABSTRAK
Area kerja Depot pasir menghasilkan bermacam-macam bahaya yang berdampak pada kesehatan
pekerjanya.. Debu merupakan salah satu faktor yang berpotensi memberikan efek buruk terhadap pekerja di
depot pasir. Debu terdiri dari partikel zat padat yang dihasilkan dari proses alamiah atau bisa disebabkan oleh
proses mekanis dari bahan-bahan alam yang mudah terurai dan tidak terurai. Debu yang dapat menganggu
mata yakni Debu Total dan PM10. Kota Palembang adalah kota yang dialiri Sungai Musi. Sungai Musi juga
menjadi tempat penambangan pasir untuk pembangunan di Kota Palembang. Beberapa penambang
melakukan aktivitasnya untuk selanjutnya dibawa ke depot-depot pasir yang ada di pinggiran Sungai Musi,
sehingga terdapat kemungkinan besar untuk pekerja terkena langsung paparan debu. Jumlah responden
sebanyak 74 orang dan data diolah dengan analisis univariat dan bivariat. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa variabel yang berhubungan adalah merokok (P value =0,002) dan indeks massa tubuh (P value
=0,002) dengan keluhan mata. Karakteristik umur responden tidak berhubungan dengan keluhan mata,
namun variable merokok dan IMT mempengaruhi kejadian keluhan mata sehingga responden sebaiknya
mengatur pola makan dan mengurangi rokok terutama saat bekerja.
Kata Kunci: Debu, Depot Pasir, Keluhan Mata
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 313
PENDAHULUAN
Lingkungan kerja sebagai tempat mencari nafkah diri sendiri maupun keluarga merupakan
tempat yang paling banyak dihabiskan waktunya oleh para pekerja. Para pekerja bisa
menghabiskan waktu dari pagi sampai malam. Kondisi demikian tentu saja tidak lepas dari potensi
bahaya, baik bahaya fisik, kimiawi maupun biologis. Bahaya inilah yang kemudian menghasilkan
suatu penyakit yang disebut dengan penyakit akibat kerja. Pekerjaan di depot pasir merupakan
pekerjaan yang berpotensi terpapar debu. Pekerjaan ini menuntut seseorang untuk melakukan
pengepulan pasir dari suatu tempat ke tempat lain. Meskipun pada saat pelaksanaannya, pekerja
menggunakan alat bantu seperti cangkul atau sekop, namun sayangnya mereka kurang
memperhatikan alat pelindung seperti masker atau kacamata. Pasalnya, paparan debu bukan hanya
mengganggu sistem pernafasan namun juga penglihatan.
Debu adalah suatu kumpulan yang terdiri dari berbagai macam partikel padat di udara yang
berukuran kasar dan tersebar, yang biasanya disebut dengan koloid. Debu termasuk ke dalam
substansi yang bersifat toksik (racun). Salah satu efek paparan debu terhadap kesehatan adalah
munculnya efek iritan, yaitu gangguan iritasi pada membrane mukosa mata dan saluran
pernafasan.1 Partikulat debu yang melayang dan berterbangan di udara akan mengakibatkan iritasi
pada mata dan dapat menghalangi daya tembus pandang mata.2 Pencemaran udara dapat
mengakibatkan iritasi mata ringan hingga berat, ketidaknyamanan penglihatan, dan meningkatkan
kepekaan terhadap cahaya.3
Mata merupakan anggota tubuh yang rumit dan sangat sensitif terhadap cahaya dan warna
yang dipancarkan oleh benda. Organ ini memiliki suatu system lensa untuk memfokuskan
bayangan dan selapis sel fotosintetif serta sel syaraf yang berperan mengumpulkan, memproses dan
meneruskan informasi yang tampak oleh penglihatan ke otak.4 Iritasi kronik dari lingkungan akibat
debu dapat menyebabkan keluhan pada mata, biasanya disebut dengan Pterygium. Mata berarir,
tampak merah dan seperti ada benda asing merupakan keluhan yang sering terjadi pada pasien.5
Pada tahun 2010 World Health Organization (WHO) mengeluarkan estimasi global terbaru
dimana 285 juta orang di dunia mengalami gangguan penglihatan dan 39 juta orang diantaranya
mengalami kebutaan.6 Hasil penelitian di Kecamatan Nongsa Batam pada masyarakat daerah
penambangan pasir menunjukkan bahwa 70% responden mengalami iritasi mata.7 Hasil penelitian
lain menyebutkan bahwa sebesar 62,5% karyawan di Pabrik Beton menderita mata merah, pedih
(81,2%), dan gatal (75%) akibat paparan debu PM10.8
Sebagaimana penjelasan diawal bahwa debu bisa terbentuk dari proses mekanis dan bisa
berdampak terhadap kenyamanan kerja dan gangguan penglihatan. Total Suspended Particulate
(TSP) merupakan debu yang bisa ditemui di sekitar perumahan. Debu yang bisa berdampak
langsung pada masyarakat adalah debu PM10, PM2,5, dan debu yang mudah terhirup serta dapat
masuk ke dalam saluran pernafasan manusia.9
Sungai Musi merupakan sebuah sungai dengan panjang 750 km yang membelah Kota
Palembang. Seberang Ilir di bagian utara dan seberang Hulu di bagian selatan. Sungai ini menjadi
tempat penambangan pasir untuk pembangunan Kota Palembang. Hampir setiap hari truk dan
mobil pengangkut pasir lalu lalang menuju dan keluar dari area depot pasir. Risiko kesehatan yang
ditimbulkang oleh aktivitas ini bukan hanya dirasakan oleh warga namun juga pekerja itu sendiri.
Pekerja Depot Pasir di Sungai Musi Kota Palembang bekerja setiap hari dengan paparan
debu yang cukup tinggi. Oleh karena itu, kajian tentang keluhan pada mata yang dialami pekerja
perlu dilakukan lebih lanjut. Agar bisa diketahui faktor apa saja yang mempengaruhinya.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 314
METODE
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan desain studi cross
sectional. Populasi penelitian adalah seluruh pekerja depot pasir di Kota Palembang. Sampel pada
studi ini adalah semua pekerja depot pasir yang berada di Kota Palembang yang diambil dengan
teknik total sampling dan memenuhi kriteria penelitian, yaitu berusia 17-60 tahun dan bersedia
menjadi responden. Jumlah responden sebanyak 74 orang dan data diolah dengan analisis univariat
dan bivariat.
HASIL PENELITIAN
Karakteristik responden pada pekerja depot pasir dalam penelitian ini meliputi usia, status
gizi, dan status merokok. Distribusi karakteristik responden pekerja depot pasir tersaji pada Tabel
1.
Tabel 1. Karakteristik Responden
Variabel Total Responden
n %
Umur ≥40 tahun 31 41,9
< 40 tahun 43 58,1
Keluhan mata Ada 52 70,3
Tidak 22 29,7
IMT
Tidak normal 32 43,2 Normal 42 56,8
Perilaku merokok Ya 48 64,9
Tidak 26 35,1
Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa lebih dari separuh responden berusia <40 tahun
(58,1%). Sebagian besar responden memiliki keluhan dengan mata (70,3%). Responden yang
memiliki indeks massa tubuh normal sebanyak 56,8%. Sebagian besar responden juga memiliki
perilaku merokok (64,9%).
Tabel 2. Kadar PM10 dan Total Suspended Particulate (TSP)
Variabel n Mean + SD Median (Min-Max) Test of normality
PM10 (mg/m3) 74 1,332 + 1,938 0,49 (0,002-9,930) <0,001
TSP (mg/m3) 74 3,393 + 6,327 6,33 (0,002-19,900) <0,001
Hasil penelitian ini juga mengamati kadar PM10 dan TSP. Berdasarkan Tabel 2 diketahui
bahwa rata-rata kadar PM10 sebesar 1,332 mg/m3, sedangkan rata-rata kadar TSP sebesar 3,393
mg/m3.
Tabel 3. Hubungan antara umur dengan keluhan mata
Umur Keluhan mata Total PR(95% CI) P-value
Ya Tidak
≥40 Tahun
<40 Tahun
20 (64,5%)
32 (74,4%)
11 (35,5%)
11 (25,6%)
31
43
0,867
(0,633-1,187)
0,508
Total 52 22 74
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 315
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 31 responden yang memiliki umur ≥40
Tahun terdapat 64,5% responden yang mengalami keluhan mata sedangkan dari 43 responden yang
memiliki umur <40 Tahun terdapat 74,4% yang mengalami keluhan mata. Dilihat dari nilai p value
0,508 hasil ini menunjukkan bahwa umur bukanlah faktor yang mempengaruhi keluhan pada mata.
Tabel 4. Korelasi antara IMT dengan keluhan mata
IMT
Keluhan mata Total PR(95% CI) P-value
Ya Tidak
Tidak normal
normal
16 (50,0%)
36 (85,7%)
16 (50,0%)
6 (14,3%)
32
42
0,583
(0,404-0,843)
0,002
Total 52 22 74
Status gizi responden dilihat dari indeks massa tubuhnya (IMT). Berdasarkan tabel diatas
diketahui bahwa dari 32 responden yang memiliki IMT tidak normal terdapat 50,0% responden
yang mengalami keluhan mata sedangkan dari 42 responden yang memiliiki IMT normal; terdapat
85,7% yang mengalami keluhan mata. Dilihat dari nilai p value 0,002 menunjukkan bahwa IMT
pekerja depot berkontribusi terhadap terjadinya keluhan pada mata.
Tabel 5. Hubungan antara perilaku merokok dengan keluhan mata
Kebiasaan merokok
Keluhan mata Total PR(95% CI) P-value
Ya Tidak
Ya
Tidak
40 (83.3%)
12 (46.2%)
8 (16.7%)
14 (53.8%)
32
42
1,806
(1,170-2,787)
0,002
Total 52 22 74
Tabel 5 memberikan informasi bahwa dari 32 responden yang merokok terdapat 83,3%
responden yang mengalami keluhan mata sedangkan dari 42 responden yang tidak memiliki
kebiasaan merokok terdapat 46,2% yang mengalami keluhan mata. Dilihat dari nilai p value 0,002
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok dengan keluhan
keluhan mata.
Tabel 6. Hubungan antara PM10 dengan keluhan mata
Pvalue PR (95%CI)
PM10 0,530 1,082 (0,846-1,384)
Tabel 6 menunjukkan hasil bahwa setiap kenaikan 1 angka PM10 beresiko untuk
mengalami keluhan mata meningkat 1,082 kali dengan 95% CI 0,846-1,384. Meskipun memiliki
risiko, namun tidak signifikan.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 316
Tabel 7. Hubungan antara TSP dengan keluhan mata
Pvalue PR (95%CI)
TSP 0,877 0,994 (0,916-1,077)
Tabel 7 menunjukkan hasil penelitian bahwa setiap kenaikan 1 angka TSP beresiko untuk
mengalami keluhan mata sebesar 0,994 kali dengan 95% CI 0,916-1,077. Ini menunjukkan bahwa
TSP tidak signifikan memberi dampak pada keluhan mata responden.
PEMBAHASAN
Karakteristik Responden
Produktivitas kerja dapat berjalan dengan optimal salah satunya dipengaruhi oleh
lingkungan kerja. Masalah kesehatan pada pekerja karena adanya bermacam-macam faktor di
lingkungan kerja tersebut, seperti faktor kimiawi, fisik, fisiologis, biologis,dan psikologis.10
Karakteristik pada penelitian ini meliputi usia, status gizi dan perilaku merokok.
Usia dengan Keluhan Mata
Penelitian ini memberikan informasi bahwa usia responden sebagian besar berada dibawah
40 tahun. Selain itu, usia bukanlah faktor yang mempengaruhi keluhan mata dikarenakan pekerja
dalam berbagai usia bisa mengalami keluhan mata. Daya tahan tubuh seseorang tidak ada yang
sama, setiap pekerja memiliki kadar toleransi yang berbeda dalam merespon paparan zat kimia
yang masuk ke dalam tubuh walaupun berada pada usia yang sama.11
Jadi tidak bisa disimpulkan
bahwa semakin bertambahnya usia, maka semakin besar pula peluang untuk mengalami keluhan
pada mata.
Status Gizi dengan Keluhan Mata
Status gizi pekerja yang dilihat dari IMT dikategorikan menjadi normal dan tidak normal.
hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IMT responden merupakan faktor yang mempengaruhi
keluhan mata. IMT yang tidak normal berkontribusi untuk memberikan dampak keluhaan mata
dikarenakan gizi yang kurang baik dapat memicu kurangnya konsentrasi dalam bekerja sehingga
berdampak pada rendahnya respon imun terhadap paparan debu. Tubuh membutuhkan vitamin dan
mineral sebagai antioksidan agar dapat membangun daya tahan tubuh.12
Mengkonsumsi makanan
bergizi setiap hari sangat penting bagi pekerja agar tercapai produktivitas kerja yang diharapkan,
karena makanan bergizi merupakan sumber energi yang menentukan gizi seseorang.13
Perilaku Merokok dengan Keluhan Mata
Perilaku merokok menunjukkan hasil yang signifikan terhadap adanya keluhan mata pada
responden. responden perokok memiliki risiko 1,8 kali untuk mengalami keluhan mata
dibandingkan yang bukan perokok. Berbagai macam keluhan kesehatan dihasilkan dari konsumsi
rokok, seperti iritasi mata, masalah pada hidung, kanker paru, asma, dan batuk berdahak.14
Hasil
penelitian pada pekerja kantoran menunjukkan adanya hubungan antara perilaku merokok dengan
sindrom mata kering.15
Hasil penelitian lain juga memberikan hasil serupa yaitu kelompok perokok
mengalami keluhan mata yang signifikan jika dibandingkan dengan kelompok yang bukan,
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 317
kemudian terdapat korelasi antara keberadaan asap rokok dengan iritasi mata seperti mata merah,
perih, berpasir, gatal dan frekuensi kedip yang signifikan.16
Kadar PM10 dengan Keluhan Mata
Pengambilan data PM10 dilakukan saat responden bekerja dan saat istirahat siang. Alat
pengukur TSP dan PM10, Haz-Dust Model EPAM-5000 diletakkan di 12 titik. Kadar NAB
maksimal PM10 menurut PERMENAKERTRANS no 13 Tahun 2011 adalah 10 mg/m3.17
Hasil
penelitian menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 angka PM10 resiko untuk mengalami keluhan
mata meningkat 1,082 kali. Artinya semakin lama terpapar dengan debu saat bekerja maka berisiko
untuk mengalami keluhan mata. Hasil penelitian ini tidak memberikan dampak yang signifikan
dikarenakan rerata kadar PM10 masih berada pada batas aman. Meskipun demikian, ditemukan
satu titik pengukuran yang memiliki PM10 pada kondisi tidak aman karena hampir mendekati
kadar bahaya yaitu depot pasir I dan II 1 Ilir sebesar 9,93 mg/m3.
Debu merupakan partikel padat yang dihasilkan dari aktivitas manusia maupun alam serta
berasal dari proses penguraian bahan produksi.18
Pada penelitian ini, debu berasal dari pasir-pasir
yang terletak di pinggir Sungai Musi. Pengamatan PM10 dilakukan di pinggir sungai, disamping
gundukan pasir dan di jalur keluar masuknya truk dan mobil pick up. Paparan debu menjadi lebih
sering dikarenakan jam kerja responden sebagian besar lebih dari delapan jam.
Partikel-partikel halus atau debu halus yang dikenal ―particulate matter‖ (PM) dihasilkan
oleh adanya debu permukaan tanah yang ditiupkan angin serta bahan-bahan yang berasal dari
permukaan gelombang. Bahan pencemar seperti debu dapat masuk ke dalam tubuh melalui mata.
Mata adalah organ penglihatan yang terbuka dengan lingkungan sekitar.19
Adanya faktor suhu,
kelembaban, kecepatan angin, dan arah angin merupakan aspek penting yang berhubungan dengan
kadar debu. Dengan kata lain, lokasi yang berbeda atau perbedaan ruang berkontribusi pada kadar
partikel debu PM10.20
Faktor musim juga berdampak pada konsentrasi partikel debu (PM10).21
Kadar TSP dengan Keluhan Mata
Debu halus yang sering disebut sebagai partikulat (TSP: Total Suspended Particulates)
adalah salah satu zat pencemar yang memberikan dampak negatif bagi tubuh. Berbagai macam zat
kimia di udara bergabung dalam partikulat tersebut. Besar atau kecilnya debu itu memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap keberadaannya di udara, semakin kecil bentuknya semakin lama
ia beredar di udara dan semkain luas sebarannya.22
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata kadar TSP melebihi angka 1, namun
tidak menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dengan keluhan pada mata pekerja depot
pasir. Jika dibandingkan dengan NAB TSP yang dikeluarkan PERMENAKERTRANS sebesar 3
mg/m3, maka rerata kadar TSP penelitian ini sebenarnya masih berisiko (3,39 mg/m
3). Temuan lain
dalam penelitian ini adalah terdapat tiga titik pengukuran yang memiliki kadar TSP yang sangat
berbahaya, yaitu depot pasir I dan II Jakabaring 15 Ulu dengan kadar tertinggi sebesar 15,38
mg/m3, depot pasir I dan II 1 Ilir sebesar 16,66 mg/m
3, dan depot pasir VII dan VIII 1 Ilir sebesar
19.90 mg/m3. Faktor curah hujan rendah atau cuaca panas dan gundukan pasir yang tinggi
membuat jumlah debu semakin banyak, sehingga risiko untuk masalah kesehatan juga semakin
tinggi. Apalagi penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker kurang dimanfaatkan. Tentu
saja akan menambah keluhan pada mata jika terlalu lama terpapar debu.
Secara umum terlihat bahwa semakin tinggi kecepatan angin, bangkitan debu jatuh dan
TSP yang terbentuk semakin tinggi pula.23
Partikulat yang beredar di udara jika tanpa sengaja
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 318
dihirup oleh manusia bisa menyebabkan penyakit.24
Menurut International Agency for Research on
Cancer (IARC) partikel TSP merupakan salah satu partikulat utama dari polusi udara yang dapat
menyebabkan kanker atau bersifat karsinogen.25
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut: faktor-faktor yang mempengaruhi keluhaan mata adalah indeks massa tubuh dan perilaku.
Usia tidak memliki efek yang signifikan terhadap keluhaan mata. Saran dari penelitian ini adalah
reponden sebaiknya mulai mengatur pola makan dan mengurangi konsumsi rokok terutama saat
bekerja agar tidak mengalami keluhaan mata. Selain itu, perlunya penggunaan APD yang sesuai
saat bekerja agar dapat mengurangi risiko masalah kesehatan dikemudian hari.
DAFTAR PUSTAKA
1. Riyadina, Woro. Efek Biologis dari Paparan Debu. Media Litbangkes Vol.VI No.01, 1996.
2. Prabowo K, Muslim B. 2018. Bahan Ajar Kesehatan Lingkungan: Penyehatan Udara.
Jakarta: PPSDMK Kemenkes RI [diakses 18 Oktober 2020].
3. Gupta SK, Gupta SC, Agarwal Renu, Sushma Srivastava, Agrawal SS, Saxena Rohit SK.
A Multicentric Case-Control Study on The Impact of Air Pollution on Eyes in a
Metropolitan City of India. Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine.
Volume 11, Nomor 1:37-40 (2007).
4. Ilyas, S. Penuntun Ilmu Penyakit Mata. Edisi 3. Jakarta: Sagung Seto; 2010. Hal 38, 116-
117, 133-137
5. Novitasari, Andra. Buku Ajar Sistem Indera Mata. Fakultas Kedokteran Universitas
Muhammadiyah Semarang. 2015. Hal 8-9.
6. Muchtar H, Triswanti N. Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pterygium Pada
Pasien Yang Berobat di RSUD DR. H. Abdoel Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2013-
2014. Jurnal Medika Malahayati Vol 2, No.1, Januari 2015 : 8 – 14.
7. Fahmaliza. Analisis lingkungan fisik dan keluhan kesehatan pada masyarakat daerah
penambangan pasir di Kecamatan Nongsa Batam tahun 2017. Skripsi. Diakses tanggal 18
Oktober 2020.
8. Pitaloka AP, Adriyani R. Paparan PM10 dan Keluhan Kesehatan Mata Pekerja Bagian
Produksi PT. Varia Usaha Beton, Sidoarjo. Jurnal Ilmiah Keperawatan Vol. 2 No. 2
(2016).
9. Bachtiar VS, Rani PSS. Analisis Debu Respirable Terhadap Masyarakat Di Kawasan
Perumahan Sekitar Lokasi Pabrik Pt. Semen Padang. Jurnal Teknik Lingkungan Unand
13(1) : 1-9 (Januari 2016).
10. Suma‘mur, PK. 2013. Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES). Jakarta:
Agung Seto
11. Ardam, KAY. Hubungan Paparan Debu Dan Lama Paparan Dengan Gangguan Faal Paru
Pekerja Overhaul Power Plant. The Indonesian Journal Of Occupational Safety And
Health, Vol. 4, No. 2 Jul-Des 2015: 155–166.
12. Siswanto, Budisetyawati, Ernawati F. Peran Beberapa Zat Gizi Mikro Dalam Sistem
Imunitas. Gizi Indon 2013, 36(1):57-64.
13. Utami, SR. Status Gizi, Kebugaran Jasmani Dan Produktivitas Kerja Pada Tenaga Kerja
Wanita. Jurnal Kesehatan Masyarakat KEMAS 8 (1) (2012) 74-80.
Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat (SNKM) 2020 319
14. Istiqomah, U. 2003. Upaya Menuju Generasi Tanpa Rokok. Surakarta: CV. Setia Aji.
15. Putantri, Hana. Hubungan antara perilaku merokok dan sindrom mata kering pada pekerja
kantoran. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Skripsi [diakses 18 Oktober
2020].
16. Tanjaya, AR, Rares L, Saerang JSM. Hubungan Pengaruh Asap Rokok Dengan Terjadinya
Keluhan Pada Mata. Jurnal Ilmiah Kedokteran Klinik Vol 1, No 2 (2013)
17. Permenakertrans Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Nilai Ambang Batas
Faktor Fisika Dan Faktor Kimia Di Tempat Kerja. www.ditjenpp.kemenkumham.go.id.
[Diakses tgl 18 Oktober 2020].
18. Mukono, HJ. 2005. Toksikologi Lingkungan. Surabaya: Airlangga University Press.
19. Sembel, DT. 2015. Toksikologi Lingkungan: Dampak Pencemaran dari Berbagai Bahan
Kimia dalam Kehidupan Sehari-hari.Yogyakarta: Penerbit Andi.
20. Zuzana, H., Jaroslav, M., Miroslav, K., dan Vitezslav, V. 2008. Identification of factor
affecting air pollution by dust aerosol PM10 in Brno City, Czech Republic. Atmospheric
Environment, 42, 8661-8673
21. Chaloulakou, A., Kassomenos, P., Spyrellis, N., Demokritou, P., dan Koutrakis P. (2002).
Measurement of PM10 and PM2.5 particle concentration in Athens, Greece. Atmospheric
Environment, 37, 649- 660
22. Sinolungan, Jehosua SV. Dampak Polusi Partikel Debu Dan Gas Kendaraan Bermotor
Pada Volume dan Kapasitas Paru. Jurnal Biomedik, Volume 1, Nomor 2, Juli 2009, hlm.
65-80
23. Yuwono AS, Mulyanto B, Kurniawan A. Penentuan Faktor Emisi Debu Jatuh Dan Partikel
Tersuspensi Dalam Udara Ambien Di Pulau Jawa. Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB
2015 Vol. I : 181–191 Isbn : 978-602-8853-27-9.
24. Rahmadini, R. Syafrudin & Andarani P. Analisis Risiko Total Suspended Particulate (TSP)
Pada Tahap Pembangunan Jalan Terhadap Kesehatan Pekerja (Studi Kasus: Pembangunan
Jalan Kendal – Batas Kota Semarang, Jawa Tengah). Jurnal Teknik Lingkungan, Vol 4, No
4 (2015).
25. International Agency for Research on Cancer (IARC). 2013. Press Release No.221
Outdoor air pollution a leading environmental cause of cancer deaths. France: World
Health Organization.