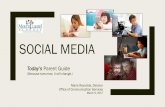Media Studies
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Media Studies
How's your view about media in society?
1. Are they free?
2. What‟s about their objectivity?
3. Are their content diverse?
4. Do The audience have choice?
5. Are their professionals autonomous?
6. Are the audience active to select the media, and the contents/programs?
7. Are their effect strong?
8. What‟s about media owner? Who are they?
9. What‟s interest they might be?
10. Can the media control the government?
1.Pers Bebas atau Media Bebas?
REP | 08 September 2014 | 09:13 Dibaca: 17 Komentar: 0 0
Informasi itu selaras dengan tanggung jawab. Dalam era yang kian berkembang dengan cepat
saat ini, setiap orang hampir memiliki kesempatan yang lebih banyak dan luas dalam
menggenggam informasi. Fakta ini menderet peluang pembagian kekuasaan, sebab salah satu
faktor dasar integritas berbangsa dan bernegara, yakni rakyat memeroleh informasi seluas-
luasnya.
Tanpa itu rakyat atau publik tidak akan memahami hak dan menjalankan kewajibannya. Alat
untuk memeroleh informasi itu adalah media yang independen dan bebas. Istilah yang biasa
dipakai adalah free press atau pers bebas, namun karena makin penting dan meningkatnya peran
media elektronik, dan jumlah warga dunia yang bergantung pada radio dan televisi istilah free
media atau media bebas lebih banyak digunakan. (Fahri Hamzah, 2012).
Banjir informasi yang ada saat ini membuat masyarakat disuguhi ragam peristiwa yang dicatat
dan dilaporkan pewarta. Publik hampir saja tidak memiliki kesempatan yang tidak mungkin
dielakkan. Sebagai misal, penulis setiap hari mencerna belasan berita di situs online, menyimak
televisi berita, mengintip isi siaran radio, dan membaca koran.
Luberan informasi itu bermuara pada satu kalimat penting, sejumlah media harus tetap berpijak
standar mutu liputan sebelum melaporkannya ke publik. Sebab kita hanya benar-benar berharap
pada media profesional dan mengabdikan diri dalam menyaring semua informasi sebelum
disajikan ke pembaca atau pemirsa. Publik selalu ingin mengetahui secara persis informasi yang
disampaikan media, apakah telah cukup adil, dan bertanggung jawab.
Media yang bebas sesungguhnya sama penting dengan sistem peradilan yang independen.
Keduanya banyak diistilahkan sebagai saudara kembar yang tidak bertanggung jawab pada
politisi, tetapi kepada publik. Keinginan untuk menarik minat pembaca, tumpukan iklan serta
untung sangat tergantung dari cara media mengelola tanggung jawabnya. Sayangnya itu
seringkali dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan di dalamnya.
Kita sedang tumbuh dalam perkembangan media baru: internet. Dimana seharusnya publik tidak
dididik dalam bisik-bisik informasi tetapi dalam kaidah dan kultur kebebasan berpendapat dan
menerima distribusi informasi secara bertanggung jawab. Sebab disanalah media menjadi hamba
pada publiknya.
Titimangsa media tengah berada pada situasi dimana jejaring sosial kerap lebih cepat
mengabarkan, dan menyulur fakta dari sisi yang berbeda dan khas. Untuk itu mau tidak mau,
kualitas wartawan atau jurnalis memasuki ruang pertarungan yang sungguh hebat. Bila media
konvesional tak mampu menyajikan informasi berimbang, dan akurat sedang jejaring media
sosial makin kuat, niscaya pembaca akan mengambil alih kuasanya.
Masyarakat pembaca yang kini memiliki kesempatan untuk menyeleksi media yang baik dan
bermanfaat, harus menjadi celah bagi pemilik media untuk meningkatkan kualitasnya. Serendah-
rendahnya strata pendidikan pembaca mereka tetap memerlukan kehadiran media yang akan
dinilainya memberi hal positif dan konstruktif. Bukan lagi era dimana ruang senyap redaksi
sebagai kastil tak tersentuh. Newsroom saat ini mesti adaptif, dan visioner.
Sebagai praktisi media, penulis tak pernah berhenti mengentalkan keprihatinan atas mutu
jurnalistik yang ada. Kebebasan pers tidak seharusnya membuat bebal. Sebab di situ ada
tanggung jawab sosial, dan efek hukum yang bisa menjerat. Bersyukurlah karena sebagian
pembaca, kalau mereka masih mau membaca, sedang bersikap pasif pada apa yang disimaknya.
Tapi percayalah publik memiliki cara bertindak.
Kelas pembaca secara jujur tidak memerlukan berita yang dibangun dari realitas duga-menduga
karena dibalik itu terselip kepentingan tertentu. Konsep hyperrality (hiper-realitas) yang
dikembangkan Jean Baudrillard dalam buku In The Shadow of The Silent Majorities untuk
menjawab dan menjelaskan perekayasaan dan distorsi informasi di dalam media (Hotman dkk,
2001).
Disebutkan, hiper-realitas menggiring orang mempercayai sebuah citra sebagai kebenaran, meski
kenyataannya hanyalah dramatisasi realitas dan pemalsuan kebenaran yang melampaui realitas.
Bila pembaca cermat, itu akan bisa dinilai akhir-akhir ini dalam isi siaran, pun kolom surat
kabar. Jika tak yakin, mulailah hari ini menjadi pembaca yang lebih kritis agar tak mudah
dibodohi. Bacalah lebih banyak sumber informasi.
Semakin jauh surat kabar atau media dari lokasi atau sumber berita, wartawan akan makin
banyak melakukan penyederhanaan yang muncul dalam bentuk simbolisasi. Keadaan ini
seharusnya disadari, sebab di luar kantor redaksi kini terdapat lebih banyak warga yang juga
mulai mengambil peran sebagai pewarta (citizen). Itu sebabnya keberpihakan hitam-putih
hampir-hampir tak lagi memiliki tempat.
Jadi berbenahlah. Proses framing berita harus dikonstruksi lebih dari sekadar teks yang
membangun, tetapi juga memberi warna, perspektif bagi pembaca. Tugas media itu menyelia
informasi, bukan saklek merunutkan kumpulan kabar sebagai kebenaran mutlak. Publiklah yang
menilai. (*)
Mamuju, 8 September 2014
http://media.kompasiana.com/new-media/2014/09/08/pers-bebas-atau-media-bebas-686297.html
2. “HILANGNYA JATI DIRI DAN OBJEKTIVITAS MEDIA MASSA DI ARUS
GLOBALISASI” Posted by Aniefy Jr Copr Kamis, 13 Juni 2013 0 comments
Mengintip Globalisasi
Sekarang ini kita menikmati kelimpahan informasi yang luar biasa. Hal ini tentu berkait
dengan makin banyak, beragam, dan cangginhnya industri media informasi dan komunikasi, mulai
cetak hingga elektronik, menawarkan berita dan sensasi. Disisi lain kita melihat kebebasan yang
dimiliki oleh penggiat media dalam berbagai pemberitaanya. Kita tentu saja dibuat bingung oleh
banyaknya berita yang diproduksi. Hal itu tidak lain karena berita yang disajiakan tiap kali
berbeda-beda bahkan berlawanan, belum lagi terkadang kita juga dibuat kaget oleh kemunculan
berita yang tampak tiba-tiba, asing dan berani (Eriyanto, 2001: V).
Dari relita diatas, kita kemudian dituntut untuk berperan aktif untuk mengetahuai apa
sebenarnaya yang terjadi dan tersembunyi dibalik teks-teks berita tersebut, tentunya dengan
bersikap objektif dan independen dalam menyikapi segala pemaknaan yang dilakukan oleh
kelompok tertentu pada kita, terlebih pada era global seperti ini.
Berbicara era Globalisasi, sudah pasti sering diidentikan dengan kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi, yang memproyeksikan dunia sebagai ‘kampung global’ (global village),
yang nyaris tanpa batas dan jarak. Pada era global, informasi dapat cepat ditransformasikan melalui
alat-alat canggih lewat media massa, baik cetak, ataupun media elektronik. Media massa tersebut
mampu mentransformasikan pesan (message) dalam waktu singkat, serentak (simultan), dan
menjangkau khalayak banyak.
Begitu besar pengaruh globalisasi sehingga para pakar di bidang ini menyebutnya sebagai
efek bola salju (snowball effect), yaitu arus global yang sulit dihindari oleh siapapun dan oleh sistem
manapun.
Pada akhirnya, globalisasi membawa perubahan yang sangat cepat di segala bidang. Karena
itu, globalisasi menuntut sikap adaptatif dengan perkembangan yang sedang berjalan. Maka siapa
yang tidak mampu beradaptasi dengan zaman, maka akan tertinggal. Perubahan sosial yang
diakibatkan oleh pengaruh globalisasi dapat mengakibatkan perubahan nilai-nilai, sistem sosial dan
tatanan masyarakat lainnya. Dengan kata lain, perubahan itu bisa berdampak pada nilai-nilai
budaya, agama dan sistem sosial politik.
Realitas yang terjadi sekarang ini, media massa -terlebih actor media- sudah tidak lagi dapat
menemukan jati diri objektivitasnya dalam menjalankan tanggung jawab sosial. Kebanyakan
pelaku media hanya terpaku dan terjebur dalam kubangan teori jurnalisme semata tanpa
menghiraukan dampak yang terjadi dalam masyarakat akibat pemberitaan yang tidak seimbang
antara realitas yang dikonstruksikan oleh satu kelompk dengan yang lain.
Berangkat dari semua itu, yang sering kita khawatirkan adalah media massa sudah
kehilangan objektivitas pemberitaannya. Harapan agar media massa melakukan self cencorhsip
sebenarnya sampai sekarang masih (diper)sulit untuk direalisasikan dalam praktik jurnalisme.
Objektivitas sebenarnaya merupakan hal yang mudah dipahami, akan tetapi sangat sulit untuk
direalisasikan, terlebih jika kita membuka mata dan melihat keadaan praktik jurnalisme di
Indonesia.
Mempertanyakan Objektivitas Media
Berbicara tentang objektivitas media massa kita tidak akan bisa melepaskan diri dari
bahasan fakta dan opini/fiksi. Westerstahl (McQuail, 2000), pernah meyodorkan bahwa yang
dinamakan objektif setidaknya mengandung faktualitas dan imparsialitas.
Faktualitas berarti kebenaran yang di dalamnya memuat akurasi (tepat dan cermat), dan
mengkaitkan sesuatu yang relevan untuk diberitakan (relevansi). Sementara itu, imparsialitas
mensyaratkan adanya keseimbangan (balance) dan kenetralan dalam mengungkap sesuatu.
Dengan demikian, informasi yang objektif selalu mengandung kejujuran, kecukupan data,
benar dan memisahkan diri dari fiksi dan opini. Ia juga perlu untuk menghindarkan diri dari
sesuatu yang hanya mengejar sensasional semata. Apa yang dikemukakan oleh Westerstahl
tersebut di atas dalam praktiknya tidak mudah untuk diwujudkan. Media massa tidak lepas dari
subjektivitas atau subjektivitas yang objektif. Subjektivitas dilakukan jika media massa
memberitakan suatu kejadian yang tidak pernah terjadi. Sementara itu, subjektivitas yang objektif
terjadi ketika media massa secara terang-terangan atau tidak cenderung membela salah satu pihak
yang sedang diberitakan. Pemberitaannya berdasarkan fakta-fakta yang terjadi (objektif) tetapi
penulisannya secara subjektif.
Kecenderungan ini mewarnai setiap kebijakan media massa. Bahkan koran sebesar New
York Times (NYT) yang sudah berusia 100 tahun dan mengawal 20 presiden AS tidak lepas dari
kepentingan itu. Noam Chomsky pernah menulis bahwa cara pandang koran itu sangatlah elitis dan
sangat menekankan kepentingan AS dalam melihat negara dunia ketiga. Dalam masalah Timor
Timur misalnya sangat sedikit ditulis sementara di Vietnam (AS punya kepentingan di sana) begitu
gencarnya. Padahal pada tahun 70-an itu, di Timor Timur terjadi banyak pelanggaran HAM yang
membutuhkan perhatian serius bagi koran sebenar NYT (Haryanto, 2006).
Apalagi media massa di Indonesia yang usianya belum setengah abad, jelas sangat tidak
mudah melakukan objektivitas penulisan. Ini bukan bermaksud membela media massa, tetapi kita
juga perlu melihat sisi lain yang mengitari media massa. Paling tidak dibandingkan dengan era
Orba, media massa Indonesia jauh lebih baik.
Selain media massa cetak, yang tidak kalah menariknya adalah objektivitas yang terjadi
pada media televisi kita dalam beberapa kasus, televisi jauh lebih besar dalam melanggar
objektivitas tayangan. Ini bisa kita lihat dari tayangan infotainment yang sedang marak di televisi
kita. Tayangan itu sering mencampuradukkan antara fakta dan opini.
Pernyataan yang dibacakan oleh narator atau pembawa acara seringkali “menuduh” pihak
tertentu dan mengarahkan penonton untuk setuju dan tidak setuju terhadap realitas yang
disajikannya. Meskipun, mereka merasa hanya sekadar memberikan ilustrasi dari apa yang
disajikan. Kata-kata seperti “sungguh tragis”, “sayangnya”, “tidak disangka” dan sebagainya menjadi
contoh kongkrit keberpihakan tersebut.
Akibat pemberitaan yang tidak proporsional itu pula, ketidakadilan di masyarakat pasti
terjadi. Meskipun demikian, realitas yang terjadi dilapangan justru masyarakat secara sadar
ataupun tidak (sengaja) terbawa arus pemberitaan yang tidak seimbang seperti infotainment,
sementara korupsi yang menimpa anggota DPR dan jajaran pemerintah sering luput dari
pengamatan kita. Bagaimana pula dengan DPRD meminta gaji yang selangit dan berkilah atas dasar
PP no. 37/2006?.
Dalam bukunya yang berjudul “Analisis Wacana Teks-Teks Media”, Eriyanto mengatakan
bahwa dalam hal ini kaum Pluralis justru melihat media massa sebagai saluran yang bebas dan
netral, di mana semua pihak dan kepentingan dapat posisi dan kepentingannya secara bebas.
Namun pandangan teresebut ditolak oleh kaum Kritis. Pandangan kritis melihat medeia bukan
hanya alat dari kelompok dominan, tetapi juga memproduksi ideology dominan. Media membantu
kelompok dominan menyebarkan gagasannya, mengontrol kelompok lain, membentuk konsesus
antar anggota komunitas. Lewat medialah, apa yang baik maupun buruk, ideology domonan
dimapankan. Media bukanlah sekedar saluran yang bebas, ia juga subyek yang mengkonstruksi
realitas, lengkap dengan bias dan pemihakannya. Seoaerti yang dikatakan pleh Tonny Bannet,
media dipandang sebagai agen konstruksi social yang mendefinisikan realitas sesuai dengan
kepentingannya.
Dalam pandangan kritis media dipandang sebagai wujud dari pertarungan ideology antara
kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Di sinilah kemudian media dikatakan bukan
merupakan sarana netral yang menampilkan kelompok da\n kekuatan dalam masyarakat secara
apa adanya, tetapi kelompok dan ideology yang domonan itulah yang akan tampil dalam
pemberitaan.
Titik penting dalam memahami media menurut paradigm kritis adalah bagaimana media
melakukan politik pemaknaan. Menurut Stuart Hall, makna tidak tergantung pada struktur makna
itu sendiri, tetapi pada praktik pemaknaan. Makna adalah suatu produksi social, suatu praktik. Bagi
stuart Hall, media massa tidak mereproduksi melainkan menentukan (to define) realitas melalui
kata-kata yang dipilih. Makna, tidaklah secara sederhana dianggap sebagai reproduks dalam
bahasa, tetapi sebuah pertentangan social (social struggle), perjuangan dalam memenangkan
wacana. Oleh karena itu pemaknaan yang berbeda merupakan arena pertarungan dimana
memasukkan bahasa didalamnya. Perjuangan antar kelompok ini melahirkan pemaknaan untuk
mengunggulkan satu kelompok dfan merendakan kelompok lain. Media disini dipandang sebagai
arena perang atar kelas. Ia adalah media diskusi public dimana masing-masing kelompok social
saling bertarung, saling menyajikan perspektif untuk memberikan pemaknaan terhadap stu
persoalan. Tentu targetnya adalah pandangannya ditrima oleh public. Media dapat dilihat sebagai
forum bertemunya semua kelompok dengan sudut pandang yang berbeda. Setiap pihak berusaha
menonjolkan basis penafsirannya, klaim dan argumentasi masing-masing agar dapat diterima oleh
public. Dalam pandangan kritis, pada akhirnya kelompok dominanlah yang lebih menguasai
pembicaraan dan menentukan arena wacana(Eriyanto, 2001: 38).
Yang menjadi persoalan dalam lalu lintas pertukaran dan produksi makna ini adalah siapa
yang memegang kendali dalam memberikan pemaknaan. Dalam realitas social, siapa yang
memegang kendali sebagai agen pemroduksi makna dan siapa atau kelompok mana yang hanya
berperan sebagai konsumen saja dari pemaknaan tersebut. Siapa yang mendefinisikan apa atau
bahkan terus menerus menjadi objek pendefinisian?. Yang sering terjadi dalam pertarungan symbol
dan pemaknaan adalah suasana tidak seimbang, satu pihak lebih mempunyai previlese dan akses
kemediadibandingkan pihak lainsehingga pemaknaan satu kelompok lebih dominan dan menguasai
media.
Melihat realitas kehidupan praktik jurnalisme seperti itu tentunya kita sebagai individu
yang memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi harus mampu memberi solusi atas semua problem
yang sudah mengakar sampai sekarang ini, terlebih kita juga merupakan pelaku media yang
sekiranya sudah dibekali cukup teori maupun pengalaman mengenai media massa secara umum.
Aniefy Jr Copr (PP. Biro Keilmuan Forkomnas KPI)
http://teraswacana.blogspot.com/2013/06/hilangnya-jati-diri-dan-objektivitas.html
Objektivitas Media dan Preferensi Audiens
Menyaksikan acara Today‟s Dialogue tanggal 22-05-2012 tempo hari di Metro TV, dapat penulis
simpulkan betapa acara tersebut menggiring pemirsa kepada opini negatif terhadap ormas Islam.
Walaupun tidak disebut-sebut ormas mana yang dimaksud oleh para pembicara, tetapi jelas
sekali dari judul acara tersebut, yaitu “Negara Tunduk Pada Kekerasan”. Walaupun kemudian
ketika acara dimulai judul (kecil) acara tersebut, ditambahkan dengan tanda tanya (?) di belakang
kalimat.
Mengapa penulis sebutkan acara tersebut tendensius memojokkan ormas Islam, hal tersebut
berkaitan dengan masalah penolakan diadakannya konser Lady Gaga oleh FPI (Front Pembela
Islam) beberapa waktu yang lalu. Terdapat dua hal yang tendensius dari acara tersebut, yaitu 1)
menyematkan stigma negatif terhadap FPI sebagai ormas yang identik dengan kekerasan atau
pelaku kekerasan, dan 2) mengarahkan pemahaman kepada lemahnya aparat negara (Kepolisian)
dalam menghadapi ormas (FPI).
Objektivitas media di sini sangat tergantung dari pemilik/pemimpin redaksi sebagai sumber
kebijakan pemberitaan. Seperti halnya Metro TV sendiri. Sebagai media televisi, menurut
penilaian penulis pada masa lalu ketika Surya Paloh (pemilik/pemimpin perusahaan) masih
tergabung dengan partai Golkar yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Soesilo Bambang
Yudhoyono (SBY), tidak pernah dalam pemberitaannya memojokkan kebijakan pemerintahan.
Paling tidak hanya bersikap netral, ketika pihak-pihak oposisi mengkritik kebijakan
pemerintahan SBY tersebut. Namun kemudian pada perkembangannya, ketika Surya Paloh tidak
lagi menjadi bagian Golkar, dengan partainya yang baru, Nasdem, sikap media tersebut
cenderung menjadi oposan terhadap SBY. Oposan yang memberikan kritik membangun, tentu
dapat disepakati adalah oposan yang baik. Namun ketika sebagai oposan yang selalu
memberikan opini negatif terhadap pemerintahan (kebijakan apapun itu), hal tersebut akan
berpengaruh terhadap preferensi audiens.
Contoh lain adalah ketika RCTI (termasuk grup MNC yang dikelola oleh Harry Tanuseodibyo
dari Nasdem), memberitakan masalah penolakan warga Yogyakarta terhadap Rancangan
Undang-Undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta yang mengarah kepada hilangnya
keistimewaan Yogyakarta. Pemberitaan dilakukan selama seminggu lebih dengan isu yang sama
sehingga menggiring audiens kepada persepsi „niat buruk‟ pemerintah pusat (SBY) terhadap
Yogyakarta.
Selain media televisi, media on line dewasa ini juga sangat berperan terhadap preferensi/opini
audiens. Sebagai contoh adalah pergolakan di negara-negara timur tengah. Mobilisasi massa
besar-besaran salah satunya dipicu oleh peran internet dalam mempengaruhi demonstrasi dan
revolusi di Mesir. Warga Mesir mulai memanfaatkan media sosial tersebut untuk
mengumpulkan massa . Dalam sebuah komik disindir adanya virus “demokrasi”dari barat yang
menyebar di internet yang kemudian memobilisasi massa untuk menjatuhkan kekuasaan absolut
Husni Mubarak[1].
Keterkaitan media terhadap preferensi publik dalam politik juga terlihat jelas. Masalah Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) DKI, misalnya, calon gubernur Joko Widodo dipersepsikan oleh
pemberitaan media, sebagai Walikota Solo yang berhasil. Dapat diduga selanjutnya, hasil
sementara perhitungan cepat (Rabu 11-07-2012) menunjukkan keunggulan Jokowi sebagai
gubernur mendatang. Padahal penduduk Jakarta tidak semuanya pernah ke Solo dan
menyaksikan sendiri keberhasilan manajerial Jokowi di sana. Walaupun relevansinya masih
perlu dikaji lebih jauh.
Uraian di atas merupakan sebagian kecil contoh kasus keterkaitan objektivitas media terhadap
preferensi audiens. Sudah seharusnya dalam pemberitaan atau segmen acara yang serupa harus
diproduksi secara objektif. Everret E. Denis dalam “Basic Issues in Mass Communication”
(1984), dalam prakteknya objektivitas pemberitaan hanya dapat dicapai dengan tiga cara: 1).
pemisahan antara fakta dan opini, 2). penyajian berita tanpa disertai dimensi emosional, dan 3.
bersikap jujur dan seimbang terhadap semua pihak[2]. Ketiga faktor objektivitas pemberitaan
tersebut, hanya akan tercapai oleh niat baik dan kecerdasan dari para jurnalis. Mengesampingkan
afiliasi politik, juga faktor suku-agama-ras-golongan (SARA), serta memahami bahwa
opini/pernyataan hipotetis bukanlah fakta. Faktor-faktor penentu objektivitas media tersebut
semakin memudar seiring dengan timbulnya kebebasan pers masa reformasi dewasa ini.
Ketidakobjektifan media terbukti dengan banyaknya pengaduan masyarakat (Islam) kepada KPI
atas tayangan Metro TV akhir September ini. Di mana 5 September 2012 Metro TV mengurai
acara dialog “Awas Generasi Baru Teroris!”, yang menyudutkan Rohis sebagai generasi baru
teroris. Sumber hidayatullah.com menyebutkan hingga Selasa, 18 September 2012, Pukul 17.09
WIB, menurut laporan dari bagian pengaduan KPI Pusat menyebutkan, angka pengaduan yang
masuk melalui SMS pengaduan di KPI Pusat mencapai 17191 SMS aduan. Sebagai catatan
penulis, tayangan dialog Metro TV atas kasus Sampang (Tajulmuluk/Syiah), cenderung
menyudutkan masyarakat Islam (Sunni), dengan hanya menyarikan informasi dari pihak Syiah
tanpa pihak Sunni sebagai pembanding.
[1] http://akusaeni.blogspot.com/2007/12/objektivitas-pemberitaan.html
[2] http://media.kompasiana.com/new-media/2012/04/20/online-media-mesin-opini-publik-
mutakhir/
https://vithakom.wordpress.com/2012/07/18/objektivitas-media-dan-preferensi-audiens/
objektivitas media massa
Media merupakan sarana manusia dalam menyampaikan dan menerima
informasi. Dalam hal ini media massa memiliki peran sentral dalam
membentuk opini public akan sebuah pemberitaan yang dipublikasikan,
baik melalui media cetak ( surat kabar/koran, majalah, tabloid, buku dan
lain-lain ), dan media elekronik ( televisi, radio, dan internet ) pesan dan
komunikasi yang berlangsung antara media dan khalayak lebih condong
membahas masalah politik, ekonomi, sosial budaya masyarakat, dan
hiburan sesuai dengan orientasi media tersebut. Namun seiring
perkembangan media massa saat ini, banyak masyarakat indonesia yang
menanyakan , dimanakah objektivitas suatu media massa dalam
mempublikasikan sebuah berita, dan bagaimanakah proses komunikasi
politik yang berlangsung antara „pemegang‟ kekuasaan dengan rakyat
yang menggunakan saluran media massa.
Hal ini menarik untuk kita mengkaji bagaimana orientasi media
massa di indonesia saat ini, apakah masih berpegang teguh pada prinsip
demokrasi yakni „bebas dan bertanggung jawab‟ atau mengikuti „arahan‟
dari sang pemilik modal perusahaan pers atau media tersebut, keduanya
memiliki ketimpangan yang jauh berbeda dimana satu sisi media dikatakan
objektif dan satu sisi lagi media hanyalah sarana yang membentuk citra
positif bagi siapa saja yang memiliki hak kuasa dalam organisasi media
atau pers tersebut.
Seperti yang telah kita ketahui selama ini, bahwa media massa
diindonesia dalam hal ini media elekronik, yaitu televisi sebagian besar
dimiliki oleh mereka yang terjun dibidang politik. Beberapa diantaranya
adalah sebagai berikut :
1. Abu rizal bakrie ( partai GolKar )
„ical‟ panggilan akrabnya, awalnya ia merupakan salah satu pengusaha
sukses dinegeri ini, dan masuk dalam daftar 10 orang terkaya untuk
kawasan Asia Tenggara, bisa dikatakan dengan pengalaman yang dimiliki
sangat mudah bagi ical dalam menginvestasi kekayaannya, ia memilih
menjadi investor terbesar diperusahaan televisi swasta, sehingga ia
berhasil „menguasai‟ 2 televisi swasta yang begitu konsisten dalam
menyiarkan berita politik terlebih lagi untuk pencitraan partai golkar
dipilpres 2014 mendatang. Tv one bisa dikatakan lebih dulu „mengiklankan‟
dan membangun citra Abu rizal bakrie sebagai calon presiden yang
diusung partai GolKar sehingga baru baru ini kita mengenal istilah ARB.
2. Surya paloh ( partai NasDem )
Kiprahnya lebih dulu dimedia massa, kemudian ia menjadi kader di partai
golkar, namun karena mengalami permasalahan internal partai, ia keluar
dan membentuk partai baru yaitu nasionalis demokrasi, yang lebih menarik
lagi ia mampu „join‟ dengan pemilik MNC group, yaitu Harry
Tanoesoedibyo, mereka bersama-sama membangun citra partai yang baru
lahir ini melalui televisi masing-masing, bisa dikatakan nasdem lebih
beruntung dalam membangun citra lewat media elektronik, sebut saja
Metro tv, MNC, RCTI, dan GLOBAL tv semuanya membangun partai
NasDem dengan slogan gerakan perubahan, sehingga tidak heran
walaupun baru lahir, namun partai ini mampu bersaing dengan partai
lainnya, bahkan sebuah lembaga survei pernah mengeluarkan hasil survey
yang mengatakan pamor Nasdem lebih tinggi dari pada Demokrat yang
hari ini diterpa badai kasus korupsi yang dilakukan kader-kader Demokrat.
Kekhawatiran masyarakat hari ini, terletak pada bagaimana sebuah
media massa yang bergantung pada sang pemiliknya, media saat ini tidak
mampu berdiri sendiri atau netral dalam menyiarkan berita ataupun
menyampaikan pesan politik, keterikatan media dengan sang pemilik
membuat media tidak mampu menjaga kredibilitasnya secara utuh, gerak-
gerik media diatur berdasarkan perintah sang pemilik, tidak bisa media itu
megeluarkan berita atau pesan yang berdasarkan fakta atau adanya
keberpihakan media dalam menyampaikan berita terhadap individu,
kelompok, atau partai politik tertentu.
Televisi swasta diindonesia pada umumya dipegang oleh mereka
yang memiliki jabatan sebagai ketua umum suatu partai politik, dengan
begitu kita bisa langsung mengetahui bagaimana suatu media membangun
partainya sendiri, dan sesekali menjatuhkan partai lawan, dan itu biasanya
berlaku ketika mulai mendekati pemilihan baik yudikatif maupun eksekutif,
begitu juga dalam menyiarkan berita seringkali kita melihat adanya
keberpihakan media terhadap individu, kelompok, atau partai politik.
Westerstahl (McQuail, 2000), pernah menyatakan bahwa yang dinamakan objektif
setidaknya mengandung faktualitas dan imparsialitas. Faktualitas berarti kebenaran yang
didalamnya memuat akurasi (tepat dan cermat), dan mengkaitkan sesuatu yang relevan untuk
diberitakan. Sementara itu, imparsialitas mensyaratkan adanya keseimbangan (balance) dan
kenetralan dalam mengungkap sesuatu. Dengan demikian, informasi yang objektif selalu
mengandung kejujuran, kecukupan data, benar, dan memisahkan diri dari fiksi dan opini. Dan
menghindarkan diri dari sesuatu yang hanya mengejar sensasional semata.
Dari pernyataan Westerstahl mengenai karakteristik media massa yang objektif, tidak
dimiliki oleh media massa khususnya media elektronik dan media cetak diindonesia hari ini,
sangat sulit bagi media kita yang sudah terikat oleh peraturan sesaat, siapa yang berkuasa dialah
yang memegang kendali, ketika adanya pergantian organisasional media tersebeut, maka
peraturan juga berganti, padahal pada hakikatnya prinsip dan peraturan merupakan pedoman atau
acuan hidup sebuah media agar dapat memiliki karakteristik yang bisa disebut objektif.
Apa yang dikemukakan oleh Westerstahl tersebut di atas dalam praktiknya tidak mudah
untuk diwujudkan. Media massa tidak lepas dari subjektivitas atau subjektivitas yang objektif.
Subjektivitas dilakukan jika media massa memberitakan suatu kejadian yang tidak pernah terjadi.
Sementara itu, subjektivitas yang objektif terjadi ketika media massa secara terang-terangan atau
tidak cenderung membela salah satu pihak yang sedang diberitakan. Pemberitaannya berdasarkan
fakta-fakta yang terjadi (objektif) tetapi penulisannya secara subjektif. padahal objektivitas suatu
berita atau pesan yang disampaikan oleh media sangat mempengaruhi paradigma atau pola pikir
masyarakat, apabila masyarakat terus menerima berita atau pesan yang berdasarkan subjektivitas,
hal itu sama saja dengan „membohongi‟ atau mengarahkan pola pikir masyarakat yang salah,
karena tidak berdasarkan fakta, atau terlebih lagi dibumbui oleh kepentingan politik, seharusnya
media dapat menyajikan berita diatas sebuah kejujuran dan fakta dari berita tersebut, tidak
memihak dan mengatakan yang sebenarnya kepada masyarakat.
Media massa sebagai pengawas mempunyai tugas untuk memunculkan berita, dan
memberikan fakta-fakta yang ada agar diketahui masyarakat. Dengan cara seperti itu diharapkan
masyarakat mengkritisi apa yang sudah diberitakan media massa tersebut. Perkara nanti mau
diproses biarlah hukum yang akan memutuskannya. Ini penting untuk dilakukan karena sistem
pemerintahan di Indonesia tidak berjalan dengan baik manakala tidak disorot media terus
menerus. Kasus korupsi yang menimpa mantan elite politik sangat jauh dari penyelesaiaan jika
media massa tidak terus-menerus mendorong untuk dilakukan pengusutannya. Di sinilah peran
penting media massa perlu didudukkan. bukan menjatuhkan atau men‟judge‟ partai politik itu
secara implisit atau eksplisit, melainkan menyajikan berita yang berimbang, tidak lantas mencari
tersangka baru, dan meyiarkan berita personal dari tersangka.
contoh kasus hari ini adalah bagaimana media massa menyudutkan partai Demokrat,
padahal bukan mantan elite politik dari partai ini saja yang tersandung masalah korupsi, masih
banyak elite politik diluar Demokrat yang lebih dulu tersandung masalah korupsi dinegeri ini,
namun media massa secara serentak memblock up berita ini secara besar-besaran, sehingga opini
pulic hari ini terbentuk bahwa partai Demokrat merupakan partai yang paling banyak kadernya
tersandung kasus korupsi, ditambah lagi pilpres yang semakin dekat, secara tidak langsung
menurunkan reputasi SBY. seandainya saja SBY, sama seperti Abu rizal bakrie, Surya paloh,
dan Harry tanoesoedibyo yang memiliki televisi swasta dinegeri ini, pastilah citra partai
Demokrat dan para elite politiknya tidak begitu terpuruk seperti yang terjadi hari ini, karena
televisi swasta tersebut akan membela, dan tidak menjatuhkan individu atau kelompok yang
berasal dari Demokrat secara frontal, kita pasti menemukan pembelaan secara tidak langsung
terhadap partai ini, namun hari ini , SBY bisa dikatakan tidak menguasai media massa secara
professional, sehingga sarana dan saluran yang paling „ampuh‟ ini tidak dapat berbuat banyak
bagi partai Demokrat.
inilah potret media massa indonesia yang terjadi hari ini, jauh dari objektivitas, dan dekat
dengan kepentingan serta subjektivitas yang berpihak pada sesuatu. tidak mencerminkan sebuah
kenetralan, dan independensi suatu media massa yang seharusnya. sulit bagia media massa kita
yang terlanjur telah dipengaruhi oleh hal-hal berbau politik dan kepentingan politik itu sendiri.
setidaknya media massa mampu menggambarkan bagaimana keadaan suatu negara, seperti
media massa indonesia yang menggambarkan kondisi negara ini yang banyak dipengaruhi oleh
para elite politik, dan ketidak sinambungan antara pemerintah dengan rakyat, atasan dengan
bawahan, dan masih banyak lagi differensiasi sosial yang terjadi dinegeri ini.
http://rahminovira.blogspot.com/2012/12/objektivitas-media-massa_13.html
3. LITERASI MEDIA
Pengarang: Apriadi Tamburaka
 Literasi media lahir dari suatu tuntutan akan pentingnya memahami dampak beragam konten
media yang menerpa khalayak media massa serta suatu upaya para khalayak konten media dan
penyedia konten media dalam menyikapi berbagai dampak konten media.
Pada dasarnya, konten media seperti dua sisi mata uang yaitu memiliki dampak positif dan dampak
negatif. Media massa baik cetak maupun elektronik menyajikan dan memenuhi kebutuhan khalayak
akan informasi dan hiburan sehingga menyajikan kejadian, peristiwa dan hiburan langsung di hadapan
kita. Pengaruh dampak negatif konten media terhadap khalayak seperti tayangan kekerasan yang dapat
ditiru oleh anak-anak, pornografi, dan bias informasi yang mempengaruhi opini, bahkan kini dengan
perkembangan teknologi informasi penggunaan jejaring sosial seperti facebook dapat disalahgunakan
untuk kejahatan.
Meskipun begitu mengabaikan atau antipati terhadap media bukan tindakan yang tepat, oleh karena
kita tetap membutuhkan konten media, yang terpenting adalah cara bijak kita dalam menyikapi
beragam media itu sendiri dan memberikan apresiasi terhadap konten media yang positif serta ikut
berpartisipasi di dalam media.
Perkembangan teknologi informasi juga membawa perubahan cara kita berkomunikasi, perubahan itu
terlihat dari pergeseran penggunaan media cetak ke media elektronik, maka mempengaruhi kecepatan,
feedback (umpan balik) informasi antara media massa dengan khalayak. Pergeseran itu juga mulai
mengubah peran dalam menyediakan konten media dari media massa kepada khalayak selaku penyedia
konten media mandiri.
Kajian literasi media di Indonesia masih terbilang baru dan masih belum terlalu berkembang, hal ini
berbeda dengan negara-negara maju yang telah lebih dulu mengembangkan kajian literasi media
menjadi fokus studi tersendiri. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya buku ini dapat memberikan
wawasan kepada pembaca dalam memahami media dan konten media, proses, dampaknya, cara
khalayak menyikapi serta cara berpartisipasi dengan konten media itu sendiri.
4. 6. Uses and Gratification Theory February 3, 2013
Filed under: college — anggidetyas @ 1:58 pm
Penelitian tentang teori uses and gratifications sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 1940an
ketika para peneliti tertarik untuk mengetahui mengapa audiens memiliki pola penggunaan
media yang berbeda-beda (Wimmer dan Dominick, 1987). Penelitian tentang uses and
gratifications pada awalnya hanya berupa penelitian deskriptif yang berusaha untuk
mengklasifikasikan respons khalayak terhadap penggunaan media ke dalam beberapa ketegori
(Berelson, Lazarsfeld, & McPhee, 1954; Katz & Lazarsfeld, 1955; Lazarsfeld, Berelson, &
Gaudet, 1948; Merton, 1949 dalam Ruggerio, 2000).
Wimmer & Dominick (1987) menyebutkan baru pada tahun 1950an hingga 1960an penelitian
uses and gratifications ini lebih menfokuskan pada identifikasi variabel-variabel psikologis dan
sosial yang diperkirakan sebagai precursors dalam perbedaan pola konsumsi media massa.
Beberapa penelitian pada periode ini,disebutkan oleh Ruggerio (2000), dilakukan oleh banyak
peneliti dengan subyek dan obyek yang bervariasi. Schramm, Lyle, dan Parker (1961) misalnya
meneliti tentang penggunaan televisi oleh anak-anak yang dipengaruhi oleh perkembangan
mental anak bersangkutan dan hubungannya dengan orangtua dan teman-temannya. Ruggerio
(2000) pun mensitasi penelitian Katz dan Foulkes (1964) dalam mengkonsepsikan penggunaan
media massa sebagai pelarian sedangkan Klapper (1963) menekankan pentingnya menganalisa
efek dari penggunaan media daripada sekedar melabeli motif penggunaan seperti yang telah
dilakukan banyak peneliti sebelumnya. Greenberg and Dominick (1969) dalam penelitian
selanjutnya menyimpulkan bahwa ras dan kelas sosial berpengaruh pada bagaimana remaja
menggunakan televisi sebagai bahan pelajaran informal.
Selama tahun 1970an penelitian dengan intens menguji motivasi audiens dan membangun
tipologi-tipologi tambahan dalam penggunaan media untuk memperoleh kepuasan sosial dan
psikologis. Hal ini merupakan jawaban dari kritik-kritik yang disampaikan oleh beberapa
ilmuwan terhadap teori uses and gratifications.
Kritik yang disampaikan oleh Elliott (1974), Swanson (1977), serta Lometti, Reeves, and Bybee
(1977) yang mengungkit bahwa teori uses and gratifications ini memiliki empat masalah
konseptual yakni ketidakjelasan kerangka konseptual, konsep mayor yang kurang tepat,
penjelasan teori pendukung yang membingungkan dan kegagalan dalam memperhitungkan
persepsi audiens terhadap konten media (Ruggerio, 2000:4). Beberapa contoh penelitian dari
periode ini antara lain penelitian Rosengreen (1974) yang menyatakan bahwan beberapa
kebutuhan dasar beinteraksi dengan karakteristik personal dan lingkungan sosial seseorang akan
menghasilkan beberapa permasalahan dan beberapa solusi. Masalah dan solusi yang ditimbulkan
ini merupakan bagian dari perbedaan motif untuk pencarian gratifikasi yang muncul dari
penggunaan media atau aktivitias lain. Secara bersamaan penggunaan media atau aktivitas lain
dapat menghasilkan gratifikasi (atau non-gratifikasi) yang memiliki efek terhadap seseorang atau
masyarakat yang akhirnya menciptakan proses yang baru.
Tahun 1980 dan 1990an banyak penelitian yang mulai menganalisa penemuan-penemuan dari
penelitian terpisah dan menganggap bahwa penggunaan media massa sebagai sebuah komunikasi
terintegrasi sekaligus fenomena sosial (Rubin dalam Ruggerio, 2000:7). Contoh-contoh yang
mendukung penelitian pada tahun-tahun ini adalah penelitian yang dilakukan Eastman (1979)
yang menganalisa hubungan antara penggunaan media televisi dengan gaya hidup audiens,
Ostman and Jeffers (1980) menguji hubungan antara motivasi penggunaan televisi dengan gaya
hidup khalayak dan genre telvisi untuk mprediksikan motivasi menonton. Bantz‟s (1982)
melakukan studi komparatif antara motivasi penggunaan media secara umum dan menonton
program televisi tertentu.
Pada tahun 1980-an pula Windahl (dalam Ruggerio, 2000:6) mengemukakan terdapat perbedaan
mendasar antara pendekatan efek secara tradisional dan pendekatan teori uses and gratifications
dimana penelitian tentang efek sebelumnya selalu berangkat dari perspektif media massa, namun
pada penelitian uses and gratifications peneliti berangkat dari perspektif khalayak. Windahl
percaya untuk menggabungkan dua pendekatan ini dengan mencari persamaan dari keduanya
dan menamai penggabungan ini dengan istiah conseffects. Berbeda dengan Webster dan
Wakshlag (dalam Ruggerio:2000) yang berupaya untuk meningkatkan validitas dari determinan
struktural dengan cara menggabungkan perbedaan perspektif antara uses and gratifiactions
dengan model pemilihan. Pendekatan ini melihat perubahan antara struktur program, pilihan
konten media dan kondisi menonton dalam proses pemilihan program. Penelitian lain juga
dilakukan oleh Dobos yang menggunakan model uses and gratifications untuk mengamati
kepuasan penggunaan dan pemilihan media dalam sebuah organisasi yang dapat
mempredikasikan pemilihan saluran telvisi dan kepuasan dengan teknologi komunikasi tertentu.
Tidak bisa dipungkiri dengan adanya perkembangan baru teknologi yang menyuguhkan khalayak
dengan banyaknya pilihan media, analisa motivasi dan kepuasan menjadi komponen yang paling
krusial dalam penelitian khalayak (Ruggerio, 2000). Setiap kali teknologi komunikasi baru
tumbuh, dalam hal ini komunikasi massa, para peneliti kemudian berlomba-lomba untuk
mengaplikasikan pendekatan uses and geratifications ini terhadap medium baru
tersebut.Contohnya adalah Donohew, Palmgreen, and Rayburn (1987) yang mengeksplorasi
bagaimana kebutuhan untuk beraktivasi berkorelasi dengan faktor-faktor sosial dan psikologis
yang berdampak pada gratifikasi yang didapatkan oleh pemirsa televisi kabel. Walker and
Bellamy (1991) meneliti tentang hubungan antara penggunaan pengendali televise jarak jauh
dengan ketertaikan audiesn terhadap program tertentu. Lin (1993) melakukan studi untuk
mengetahui jika kepuasaan penggunaan VCR, frekuensi dan durasi penggunaan VCR dan
komunikasi antarpersonal tentang VCR berhubungan dengan tiga fungsi VCR yakni hiburan,
teknologi pengganti televisi dan utilitas social. Jacobs (1995) menguji hubungan antara
karakteristik sosiodemografis khalayak dan kepuasan menonton pada pemirsa televise kabel.
Perse dan Dunn (1998) meneliti tentang penggunaan computer dan bagaimana kepemilikan CD-
Rom dan fasilitas internet dapat berpenganruh tentang kegunaan komputer. Matthias Rickes,
Christian von Criegern, Sven Jöckel (2006) meneliti tentang gratifikasi yang didapatkan dari
penggunaan situs-situs internet.
Benang merah tentang penerapan teori uses and gratifications dalam media ini diungkapkan oleh
Williams, Phillips, & Lum pada tahun 1985 (dalam Ruggerio, 2000) bahwa setiap peneliti ingin
mengetahui apakah media baru dapat memenuhi kebutuhan khalayak yang sama dengan media
konvesional yang telah diuji sebelumnya. Ruggerio (2000) sendiri menganggap bahwa dengan
banyak pilihan media di masyarakat maka perlu diteliti alasan khalayak untuk terus
mengkonsumsi media tertentu dan gratifikasi apa yang mereka dapatkan dari penggunaan media
tersebut.
Model Uses and Gratification ini menunjukkan bahwa yang menjadi permasalahan utama
bukanlah bagaimana media mengubah sikap dan perilaku khalayak, tetapi bagaimana media
memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial khalayak (Uchjana, 1993: 289-290).
Studi dalm bidang ini memusatkan perhatian pada penggunaan (uses), media untuk mendapatkan
kepuasan (gratification) atas kebutuhan sesorang,maka perilaku khalayak akan dijelaskan
melalui berbagai kebutuhan (needs) dan kepentingan individu.
Khalayak/penonton dianggap individu yang aktif, selektif dan memiliki tujuan tertentu terkait
dengan terpaan media kepadanya. Artinya individu atau audiens (khalayak) sebagai makhluk
sosial mempunyai sifat selektif dalam menerima pesan yang ada dalam media massa. Audiens
yang menerima pesan tidak serta merta lagi menerima semua pesan, informasi dari media seperti
halnya dalam teori peluru dan model jarum hipodermik melainkan audiens menggunakan media
tersebut hanya sebatas memenuhi kebutuhannya sehingga menciptakan kepuasaan dalam dirinya
untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.
Riset yang dilakukan dengan pendekatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 1940-an oleh
Paul Lazarfeld yang meneliti alasan masyarakat terhadap acara radio berupa opera sabun dan
kuis serta alasan mereka membaca berita di surat kabar (McQuail, 2002 : 387).
Kebanyakan perempuan yang mendengarkan opera sabun di radio beralasan bahwa dengan
mendengarkan opera sabun mereka dapat memperoleh gambaran ibu rumah tangga dan istri yang
ideal atau dengan mendengarkan opera sabun mereka merasa dapat melepas segala emosi yang
mereka miliki. Sedangkan para pembaca surat kabar beralasan bahwa dengan membeca surat
kabar mereka selain mendapat informasi yang berguna, mereka juga mendapatkan rasa aman,
saling berbagai informasi dan rutinitas keseharian (McQuail, 2002 : 387).
Riset yang lebih mutakhir dilakukan oleh Dennis McQuail dan kawan-kawan dan mereka
menemukan empat tipologi motivasi khalayak yang terangkum dalam skema media – persons
interactions sebagai berikut :
Diversion, yaitu melepaskan diri dari rutinitas dan masalah; sarana pelepasan emosi
Personal relationships, yaitu persahabatan; kegunaan sosial
Personal identity, yaitu referensi diri; eksplorasi realitas; penguatan nilai
Surveillance (bentuk-bentuk pencarian informasi) (McQuail, 2002 : 388).
Sebanyak apapun tayangan yang tidak mendidik, apabila khalayak menganggapnya tidak penting
dan tidak akan memberikan „keuntungan‟ bagi mereka, tidaklah berpengaruh negatif.
Perkembangan teori Uses and Gratification Media dibedakan dalam tiga fase (dalam
Rosengren dkk., 1974), yaitu:
Fase pertama, ditandai oleh Elihu Katz dan Blumler (1974) memberikan deskripsi tentang orientasi subgroup audiens untuk memilih dari ragam isi media. Dalam fase ini masih terdapat kelemahan metodologis dan konseptual dalam meneliti orientasi audiens.
Fase kedua, Elihu Katz dan Blumler menawarkan operasionalisasi variabel-variabel sosial dan psikologis yang diperkirakan memberi pengaruh terhadap perbedaan pola–pola konsumsi media. Fase ini juga menandai dimulainya perhatian pada tipologi penelitian gratifikasi media.
Fase ketiga, ditandai adanya usaha menggunakan data gratifikasi untuk menjelaskan cara lain dalam proses komunikasi, dimana harapan dan motif audiens mungkin berhubungan.
Menurut para pencetusnya Elihu Katz, Jay G. Blumler dan Michael Gurevitch menguraikan
lima elemen atau asumsi-asumsi dasar dari Uses and Gratification Media sebagai berikutb
(dalam Baran dan Davis, 2000) :
1. Audiens dianggap aktif, dan penggunaan media berorientasi pada tujuan. Artinya khalayak
sebagai bagian penting dari penggunaan media massa diasumsikan mempunyai tujuan.
2. Inisiative yang menghubungkan antara kebutuhan kepuasan dan pilihan media spesifik
terletak di tangan audiens.
3. Media bersaing dengan sumber-sumber lain dalam upaya memuaskan kebutuhan
audiens, kebutuhan yang dipenuhi media lebih luas, bagaimana kebutuhan ini terpenuhi melalui
konsumsi media amat bergantung pada perilaku audiens yang bersangkutan.
4. Tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang diberikan anggota khalayak
atau audiens, artinya orang dianggap cukup mengerti untuk melaporkan kepentingan dan motif
pada situasi-situasi tertentu.
5. Penilaian tentang artikultular dari media massa harus ditangguhkan sebelum diteliti
lebih dahulu orientasi khalayak.
Elihu Katz, Jay G. Blumler dan Michael Gurevitch, juga menjelaskan uses and gratification
theory meneliti asal mula kebutuhan secara psikologis dan sosial, yang menimbulkan harapan
tertentu dari media massa atau sumber-sumber lain, yang membawa pada pola terpaan media
yang berlainan (atau keterlibatan pada kegiatan lain), dan menimbulkan pemenuhan kebutuhan
dan akibat-akibat lain.
McQuail (1995) mengatakan ada dua hal yang utama yang mendorong munculnya
pendekatan penggunaan ini. Pertama, ada oposisi terhadap pandangan deterministis tentang efek
media. Kedua, ada keinginan untuk lepas dari debat yang berkepanjangan tentang sslera media
massa.
Model-model kegunaan dan gratifikasi dirancang untuk menggambarkan proses penerimaan
dalam komunikasi massa dan menjelaskan penggunaaan media oleh individu atau kelompok-
kelompok individu.
Kritik Teori Uses and gratification
Pada derajat tertentu laporan penggunaan media oleh para pemirsanya memiliki keterbatasan-
keterbatasan. Banyak orang tidak benar-benar tahu alasan mengapa mereka memilih media atau
saluran tertentu, contohnya anak-anak hanya tahu bahwa mereka menghindari menonton saluran
yang menayangkan bincang-bincang orang dewasa, atau film berbahasa asing karena mereka
tidak mengerti, tetapi anak-anak tersebut tidak benar-benar sadar mereka berakhir di saluran
mana.
Walaupun teori ini menekankan pemilihan media oleh para pemirsanya, namun ada penelitian-
penelitian lain yang mengungkapkan bahwa penggunaan media sebenarnya terkait dengan
kebiasaan, ritual, dan tidak benar-benar diseleksi Teori ini mengesampingkan kemungkinan
bahwa media bisa jadi memiliki pengaruh yang tidak disadari pada kehidupan pemirsanya dan
mendikte bagaimana seharusnya dunia dilihat dari kacamata para perancang kandungan isi dalam
media.
Sebagai contoh saat anak-anak pulang sekolah, sudah menjadi kebiasaannya untuk mengambil
makan siang dan duduk dikursi sembari menyetel TV. Tidak ada alasan yang benar-benar nyata
mengapa ia menyetel TV dan bukannya membaca majalah atau koran, hanya kebiasaan, atau
justru sebaliknya, bagi orang dewasa mungkin ia langsung membaca koran dan bukannya
menyetel TV saat meminum kopinya dipagi hari. Pada banyak hal kejadian ini merupakan
kejadian alamiah sehari-hari dan tidak dilakukan secara sadar. Walaupun begitu menonton TV
dapat juga menjadi pengalaman seni dan menggugah motivasi seseorang untuk melakukan
sesuatu.
Namun sebuah teori yang menyatakan bahwa pemirsa media sebenarnya hanya menggunakan
media untuk menyalurkan pemenuhan akan kepuasannya sejujurnya tidak secara penuh dapat
menilai kekuatan media dalam lingkup sosial di masa kini. Teori Penggunaan dan Pemenuhan
Kepuasan dapat dikatakan tidak sempurna saat digunakan untuk menilai media yang telah
digunakan secara ritual (kebiasaan). Namun teori ini tetap tepat untuk digunakan untuk menilai
hal-hal spesifik tertentu yang menyangkut pemilihan pribadi saat menggunakan media.
Pengujian-pengujian terhadap asumsi-asumsi Uses and Gratification Media menghasilkan enam
(6) kategori identifikasi dan temuan-temuannya (dalam Rosengren dkk., 1974), sebaga berikut:
1. Asal usul sosial dan psikologis gratifikasi media.
John W.C. Johnstone (1974) menganggap bahwa anggota audiens tidak anonimous dan sebagai
individu yang terpisah, tetapi sebagai anggota kelompok sosial yang terorganisir dan sebagai
partisipan dalam sebuah kultur. Sesuai dengan anggapan ini, media berhubungan dengan
pemenuhan kebutuhan dan keperluan individu-individu, yang tumbuh didasarkan lokalitas dan
relasi sosial individu-individu tersebut.
Faktor-faktor psikologis juga berperan dalam memotivasi penggunaan media. Konsep-konsep
psikologis seperti kepercayaan, nilai-nilai, dan persepsi mempunyai pengaruh dalam pencarian
gratifikasi dan menjadi hubungan kausal dengan motivasi media.
2. Pendekatan nilai pengharapan.
Konsep pengharapan audiens yang perhatian (concern) pada karakteristik media dan potensi
gratifikasi yang ingin diperoleh merupakan asumsi pokok Uses and Gratification Media
mengenai audiens aktif. Jika anggota audiens memilih di antara berbagai alternatif media dan
non media sesuai dengan kebutuhan mereka, mereka harus memiliki persepsi tentang alternatif
yang memungkinkan untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Kepercayaan terhadap suatu media
tertentu menjadi faktor signifikan dalam hal pengharapan terhadap media itu.
3. Aktifitas audiens.
Levy dan Windahl (1984) menyusun tipologi aktifitas audiens yang dibentuk melalui dua
dimensi:
o Orientasi audiens: selektifitas; keterlibatan; kegunaan. o Skedul aktifitas: sebelum; selama; sesudah terpaan ( baca handsout ”audiens”)
Katz, Gurevitch, dan Haas (1973) dalam penelitian tentang penggunaan media, menemukan
perbedaan anggota audiens berkenaan dengan basis gratifikasi yang dirasakan. Dipengaruhi
beberapa faktor. Yaitu: struktur media dan teknologi; isi media; konsumsi media; aktifitas non
media; dan persepsi terhadap gratifikasi yang diperoleh.
Garramore (1983) secara eksperimental menggali pengaruh ”rangkaian motivasi pada proses
komersialisasi politik melalui TV. Ia menemukan bahwa anggota audience secara aktif
memproses/mencerna isi media, dan pemrosesan ini dipengaruhi oleh motivasi.
4. Gratifikasi yang dicari dan yang diperoleh.
Pada awal sampai pertengahan 1970-an sejumlah ilmuwan media menekankan perlunya
pemisahan antara motif konsumsi media atau pencarian gratifikasi (GS) dan pemerolehan
gratifikasi (GO). Penelitian tentang hubungan antara GS dan GO, menghasilkan temuan sebagai
berikut GS individual berkorelasi cukup kuat dengan GO terkait. Di lain pihak GS dapat
dipisahkan secara empiris dengan GO, seperti pemisahan antara GS dengan GO secara
konseptual, dengan alasan sebagai berikut:
o GS dan GO berpengaruh, tetapi yang satu bukan determinan bagi yang lain. o Dimensi-dimensi GS dan GO ditemukan berbeda dalam beberapa studi. o Tingkatan rata-rata GS seringkali berbeda dari tingkatan rata-rata GO. o GS dan GO secara independen menyumbang perbedaan pengukuran konsumsi media
dan efek.
Penelitian GS dan GO menemukan bahwa GS dan GO berhubungan dalam berbagai cara dengan
variabel-variabel: terpaan; pemilihan program dependensi media; kepercayaan; evaluasi terhadap
ciri-ciri atau sifat-sifat media.
5. Gratifikasi dan konsumsi media.
Penelitian mengenai hubungan antata gratifikasi (GS-GO) dengan konsumsi media terbagi
menjadi dua kategori utama, yaitu:
o Studi tipologis mengenai gratifikasi media. o Studi yang menggali hubungan empiris antara gratifikasi di satu sisi dengan pengukuran
terpaan media atau pemilihan isi media di sisi lain.
Studi-studi menunjukkan bahwa gratifikasi berhubungan dengan pemilihan program. Becker dan
Fruit memberi bukti bahwa anggota audiens membandingkan GO dari media yang berbeda
berhubungan dengan konsumsi media. Studi konsumsi media menunjukkan terdapat korelasi
rendah sampai sedang antara pengukuran gratifikasi dan indeks konsumsi.
6. Gratifikasi dan efek yang diperoleh.
Windahl (1981) penggagas model uses and effects, menunjukkan bahwa bermacam-macam
gratifikasi audiens berhubungan dengan spectrum luas efek media yang meliputi pengetahuan,
dependensi, sikap, persepsi mengenai realitas social, agenda setting, diskusi, dan berbagai efek
politik.
Blumer mengkritisi studi uses and effects sebagai kekurangan perspektif. Dalam usaha untuk
menstimulasi suatu pendekatan yang lebih teoritis, Blumer menawarkan tiga hipotesis sebagai
berikut:
- Motivasi kognitif akan memfasilitasi penemuan informasi.
- Motivasi pelepasan dan pelarian akan menghadiahi penemuan audiens terhadap persepsi
mengenai situasi sosial.
- Motivasi identitas personal akan mendorong penguatan efek.
Sumber:
(Komunikasi Massa suatu pengantar, Drs. Elvinaro Ardianto, M.si., dkk.)
(http://www.syukrie.co.cc/2010/06/use-and-gratification-theory-teori_12.html)
(http://adiprakosa.blogspot.com/2007/11/uses-gratification.html)
(http://www.wikipedia.org)
(http://jurusankomunikasi.blogspot.com/2009/04/teory-komunikasi-massa.html)
7. Efek media
Teori Efek (Effect Theory) Komunikasi
Media Massa
Diposkan oleh Malista... | Label: Komunikasi Massa
undefined
undefined
Penelitian tentang pesan kekerasan di media terhadap anak-anak ini, membahas Powerful Effect.
Alasannya adalah karena selanjutnya peneliti memakai teori kultivasi untuk mengukur dampak
kekerasan media terhadap anak-anak, dengan pemikiran bahwa media akan berpengaruh bagi anak-
anak baik secara kognitif, afektif, maupun behavioral (Hipodermic Needle Theory). Berikut ini adalah
penjelasan historis mengenai teori efek:
Powerful Effect
Pada mulanya para peneliti kamonukasi percaya pada teori Hipodermic Needle atau yang mirip
dengan itu, teori Magic Bullet. Dalam teori Magic Bullet, media seperti sebuah pistol yang
menembakkan pesan kepada khalayak (audience). Sedangkan teori Hipodermik Needle menggunakan
analogi yang berbeda yaitu dengan mengumpamakan media seperti jarum yang menyuntikkan pesan
kepada khalayak. Kedua metafora ini menyatakan bahwa penyebab individu-individu berpikir dan
berperilaku adalah merujuk pada pesan yang mereka terima. Jadi, teori-teori ini berpendapat bahwa
media begitu kuat sehingga mereka dapat langsung mempengaruhi khalayak sesuai dengan cara yang
dimaksudkan oleh pendesain pesan. Pendeknya, para peneliti di era awal perkembangan ilmu
komunikasi ini berasumsi bahwa media memiliki kekuatan untuk memberitahu orang tentang apa yang
harus dipikir dan bagaimana harus berperilaku.
Teori ini memiliki kelemahan yaitu semua khalayak dianggap sama, baik dalam berpikir maupun
berperilaku. Perbedaan usia, ras, etnis, jenis kelamin, atau status sosial dan ekonomi tidak
mempengaruhi cara orang mengintepretasikan informasi yang diterima dari media. Para peneliti
tersebut tidak memperhitungkan fakta bahwa orang mungkin bereaksi berbeda pada pesan yang sama.
Khalayak dianggap pasif dan dapat dimanipulasi (Baldwin, Perry & Moffitt, 2004, hlm.194-195). Oleh
karena itu, Raymond Bauer kemudian menyangkalnya dan engatakan bahwa khalayak media
sebenarnya “keras kepala”. Bauer juga mengatakan banyak variabel yang dapat membentuk efek dalam
bermacam-macam cara (Littlejohn & Foss, 2005, hlm.298).
Teori Hipodermic Neddle kemudian diikuti dengan model Two-Step Flow. Disini khalayak tidak
semata-mata hanya dipengaruhi oleh media saja melainkan diakui adanya Opinion Leaders. Wright
mengatakan individu-individu yang, lewat kontak dari hari ke hari, mempengaruhi orang-orang lain
dalam pengambilan keputusan dan pembentukan pendapat (Tubbs & Moss, 2000, hlm.208). Individu-
individu tersebut misalnya keuarga, teman, rekan kerja, dan lain-lain. Model Two-Step Flow pun lama-
lama berkembang dan memunculkan model Multi-Step Flow.
Limited Effect
Scharmm dan Roberts (1971, hlm.191) melukiskan pandangan baru mengenai khlayak komunikasi
masa kini: Suatu khalayak yang sangat aktif mencari apa yang mereka inginkan, menolak lebih banyak isi
media, daripada menerimanya, berinteraksi dengan anggota-anggota kelompok yang mereka masuki
dengan isi media yang mereka terima, dan sering menguji pesan media massa dengan
membicarakannya dengan orang-orang lain atau membandingkannya dengan isi media lainnya (Tubbs &
Moss, 2000, hlm.209).
Meski teori Limited Effects meruntuhkan asumsi-asumsi Powerful Media, mereka menegaskan
pengaruh dari hubungan-hubungan sosial dan proses psikologis individual. Para peneliti lebih lagi
berkonsentrasi pada perbedaan di antara individu-individu dalam sebuah khalayak, seperti perbedaan
usia, ras, etnis, dan jenis kelamin. Mereka juga mulai mempertimbangkan pengaruh-pengaruh sosial,
seperti keanggotaaan politik, agama, dan terutama status ekonomi. Banyak peneliti setuju pada klaim
Joseph Klapper (1960) bahwa media hanya merupakan salah satu bagian dari sebuah puzzle, dan
perhatian lebih diberikan pada bagaimana individua-individu menginterpretasi pesan-pesan dan
bagaimana jenis-jenis pengauh sosial lainnya membentuk persepsi (Baldwin, Perry & Moffitt, 2004,
hlm.195-196).
Moderate Effect
Inti dari perspektif ini adalah gagasan mengenai khalayak aktif yang menggunakan isi media untuk
menciptakan pengalaman (Bryant & Street, 1988). Perspektif Moderat Effect menyatakan pentingnya
pengaruh media dapat terjadi pada masa yang lebih lama sebagai sebuah akibat langsung dari khalayak.
Khalayak dapat membuat media menyajikan tujuan pasti, seperti menggunakan media untuk
mempelajari informasi dan memperoleh pengalaman.
Perspektif ini adalah kelanjutan dari teori Limited Effect yang menekankan adanya selektivitas
yang dilakukan khalayak dalam mengkonsumsi media. Perspektif ini membahas tentang selective
exposure, yaitu suatu kecenderungan untuk memilih komunikasi yang akan menegaskan pendapat,
sikap, dan nilai-nilai diri sendiri. Orang cenderung menyukai dan mencari orang-orang yang
kepercayaan, sikap, dan nilai-nilainya serupa dengan dirinya, dan tidak menyukai serta menghindari
orang-orang yang dipandang berbeda dalam hal-hal ini (Tubbs & Moss, 2000, hlm.209-210).
Peneliti mulai menguji bagaimana orang-orang menginterpretaikan pesan secara berbeda melalui
selective attention, sellective perception, dan selective retention. Ini berarti para peneliti mulai menguji
pesan seperti apa yang menarik orang-orang, mengapa orang-orang memiliki interpretasi yang berbeda-
beda pada pesan yang sama, dan mengapa orang mengingat hal-hal yang berbeda-beda dari sebuah
pesan (Baldwin, Perry & Moffitt, 2004, hlm.195).
Sepanjang tahun 1970 dan 1980, para peneliti kembali berpikir bahwa media bisa saja memainkan
peranan yang kuat. Mereka mengakui bahwa efek media mungkin terbatas, tapi di beberapa area efek
yang kuat mulai terlihat (Baldwin, Perry & Moffitt, 2004, hlm.196).
Mungkin tokoh yang paling vokal pada era ini adalah Elisabeth Noelle-Neumann. Noelle-Neumann
percaya bahwa teori limited effect telah mengubah interpretasi hasil-hasil penelitian selama bertahun-
tahun. Ia juga mengatakan bahwa dogma “ketidakberdayaan media” tidak lagi dapat dipertahankan. Ia
menyatakan sejarah teori komunikasi bagai pendulum, yang berayun dari pekerjaan Klapper yang
terkenal sampai pada saat ini, yaitu kebanyakan para peneliti percaya bahwa media memiliki kekuatan
untuk mempengaruhi (Littlejohn & Foss, 2005, hlm.299).
Paradigma limited but powerfull effect mengakomodasi beberapa dari teori-teori limited effect
juga beberapa dari model-model powerful effect. Teori dependensi media, framing, dan agenda setting
merefleksikan ide bahwa efek media terbatas hanya pada satu dimensi dari sebuah topik dan tidak
menghubungkan pengaruh yang luas kepada media. Apa yang bisa dikatakan penelitian limited but
powerfull effect adalah bahwa media kadang memainkan peranan yang kuat dalam membentuk ide dan
perilaku orang-orang, kadang media hanya berpengaruh kecil terhadap khalayak (Baldwin, Perry &
Moffitt, 2004, hlm.197).
Sumber:
Baldwin, John R; Stephen D.P; Mary A.M. (2004). Communication Theories for Everyday Life. United States of
America: Pearson Education, Inc:.
Littlejohn, Stephen W; Karen A.F. (2005). Theories of Human Communication. Thomson.
Tubbs, Stewart L; Sylvia M. (2000). Human Communication: konteks-konteks komunikasi, buku 2, terjemahan:
Deddy Mulyana. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
9. Ketertarikan pemilik media
Konglomerasi Media Dan Intervensi Pemilik Terhadap Media
Oleh Debby Kurniadi
1. Latar Belakang
Informations is commodity and power. Di era globalisasi saat ini informasi tidak lagi menjadi
kebutuhan sekunder, tetapi telah mengalami transisi sebagai komoditas utama bagi khalayak.
Mereka yang menguasai informasi adalah mereka yang memiliki power, kalimat tersebut sudah
menjadi pembahasan hari-hari masyarakat yang juga memperkuat betapa pentingnya informasi
sebagai suatu kebutuhan.
Media merupakan bagian dari komunikasi massa yang tentunya memegang posisi penting
dalam percepatan menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat. Mengingat pentingnya
media sebagai saluran dalam menyampaikan informasi tentunya tidak lepas dari fungsi utama
media. Menurut Samuel L. Becker (1985) ada tujuh fungsi komunikasi massa terhadap individu,
sebagai berikut:
Pengawasan atau pencarian informasi Mengembangkan konsep diri Fasilitas dalam hubungan sosial Subtitusi dalam hubungan sosial Membantu melegakan emosi Sarana pelarian dari ketegangan dan keterasingan Sebagai bagian dari kehidupan rutin atau ritualisasi (dalam Yasir, 2009)
Kebutuhan masyarakat akan informasi telah menjadikan industri media berkembang pesat,
tidak saja di negara maju tetapi juga di Indonesia pasca Reformasi dengan isunya “Kebebasan
Pers”. Media lokal pun seakan-akan tidak ingin kehilangan moment ini, seperti halnya Riau Pos
Group dan beberapa media lainnya yang ada di Provinsi Riau.
Pesatnya perkembangan media massa saat ini, juga menjadikan media tidak lagi sebagai
institusi yang ideal dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang, sebagai alat
sosial, politik, budaya dan fungsinya dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan regulasi.
Tetapi telah berubah menjadi institusi yang menjanjikan secara ekonomi bagi para pengusaha.
Begitu juga halnya dengan kepentingan pemilik media, yang mampu menggiring opini
masyarakat tehadap suatu realitas. Hal ini bertambah “tidak baik” dengan adanya beberapa
perusahaan berskala besar yang memiliki unit usaha berbagai media. Sehingga pemilik media
mampu mempengaruhi masyarakat dengan media yang dimiliknya, dan tidak jarang beberapa
media memiliki konten informasi yang sama. Hal ini disebut juga dengan konglomerasi media,
sehingga sulit bagi masyarakat pada saat ini untuk mencari media yang benar-benar netral dan
bertanggung jawab.
2. Konglomerasi Media
Konglomerasimedia merupakan kekuatan dari perusahaan yang berskala besar dalam memiliki
banyak dan jenis media massa sebagai bagian bisnisnya. Tentu saja konglomerasi media ini
sangat tidak sehat dalam iklim demokrasi mengingat kekuatan media (power full) yang sangat
berpengaruh terhadap masyarakat yang menkonsumsi informasi dari media media tersebut.
Bentuk konglomerasi ini tentunya sudah terjadi di Indonesia, sebut saja PT Media Nusantara
Citra,Tbk yang memiliki RCTI, MNC TV, Global TV, Radio Trijaya, Koran Seputar Indonesia,
Okezone.com dan Indovision. MNC Group ini dimiliki oleh Hary Tanoesoedibyo yang memiliki
latar belakang tidak saja sebagai seorang pengusaha tetapi juga tokoh politik.
Kemudian Visi Media Asia (Viva Group) yang dimiliki oleh putra Abu Rizal Bakrie yakni Anindya
Bakrie yang menaungi Vivanews.com, TV One dan ANTV. Surya Paloh juga memiliki Metro TV
dan Media Indonesia yang bernaung dibawah Group Media Indonesia. Pemilik dua perusahaan
besar ini adalah pelaku binis dan sekaligus sebagai tokoh politik di Indonesia.
Sementara CT Corp yang sebelumnya bernama Para Group milik Chairul Tanjung, tidak saja
menaungi beberapa perusahaan dibidang Perbankan, Pasar Modal, Pembiayaan, Asuransi,
Perhotelan, Property dan Retail ini juga memiliki unit usaha media massa. Sebut saja
Detik.com, Trans TV dan Trans 7 yang sebelumnya bernama TV 7 milik Kompas Gramedia
Group.
Pelaku bisnis media lokal pun seakan tidak ingin ketinggalan, seperti Riau Pos Group yang
dimiliki oleh Rida K Liamsi ini mememiliki unit bisnis media seperti Koran Harian Pagi Riau Pos,
Pekanbaru Pos, Pekanbaru MX, Dumai Pos, Xpresi Magazine, Riau TV dan Fresh Radio.
Dalam mengembangkan bisnis medianya, Riau Pos Group telah memperluas jaringannya
kebeberapa provinsi di Sumatera. Seperti Batam Pos, Tanjung Pinang Pos, Posmetro Batam,
Batam TV, Padang Ekspres, Posmetro Padang, Padang TV, Triarga TV, Sumut Pos dan
Posmetro Padang.
Singkat kata, nama-nama pemilik media diatas merupakan orang-orang yang membangun
kerajaan bisnis mereka dengan berupaya dekat dengan kekuasaan. Malah beberapa diantara
mereka adalah tokoh politik yang tentunya memiliki kepentingan dan tujuan. Akibatnya media
yang mereka miliki tentunya lebih mengutamakan informasi dan tayangan menarik ketimbang
informasi dan tayangan yang penting bagi masyarakat.
Ataupun karena adanya intervensi dari pemilik media tersebut, konten informasi yang
disampaikan oleh media pun akan menjadi bias. Baik itu kepentingan ekonomi, politik dan
ideologi sang pemilik, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mencari informasi dan tayangan
yang netral dan realitas yang sesungguhnya. Dengan kondisi ini maka terlihat jelas
Konglomerasi media memiliki peran penting dalam menyaring informasi dan tayangan apa saja
yang boleh dan tidak boleh disampaikan kepada masyarakat.
Media massa mampu memilih dan menetapkan isu yang akan mereka sampaikan kepada
masyarakat. Dengan adanya penekanan pada isu-isu tertentu oleh media massa akan mampu
menggiring atau justru merubah opini masyarakat terhadap realitas yang terjadi. Media mampu
menggiring opini masyarakat terhadap suatu isu, dan kemampuan media dalam mempengaruhi
perubahan kognitif individu ini menjadi salah satu aspek terpenting dari kekuatan komunikasi
massa.
Teori Agenda Setting ditemukan oleh McComb dan Donald Shaw sekitar tahun 1968. Teori ini
berasumsi bahwa media mempunyai kemampuan untuk mentransfer isu untuk mempengaruhi
agenda publik. Khalayak akan menganggap suatu isu tersebut penting, karena media
menganggap isu tersebut penting (dalam Syaiful Rohim, 2009).
Dengan adanya kepemilikan media oleh segelintir orang ini, tentunya akan menimbulkan
dampak negatif, pada kelangsungan system media di Indonesia. Konglomerasi media ini juga
tentunya sangat bertentangan dengan fungsi dan etika media yang seharusnya.
3. Intervensi Ekonomi Dan Politik Pemilik Terhadap Media
Saat ini masyarakat Indonesia menjadikan media massa sebagai salah satu jembatan informasi
mengenai berbagai hal dan realitas dimasyarakat. Baik itu media massa seperti koran, bulletin,
majalah, televisi, radio ataupun film. Begitu pula halnya dengan masyarakat yang ada di
Provinsi Riau, membaca koran sambil menikmati secangkir kopi dipagi hari seakan-akan telah
menjadi ritual sebagian masyarakat.
Kondisi ini tentunya sangat sesuai dengan Teori Depensi Mengenai Efek Komunikasi Massa
yang dikembangkan oleh Sandra Ball-Rokeach dan Melvin L DeFleur (1976). Yang
memfokuskan perhatiannya pada kondisi struktural suatu masyarakat yang mengatur
kecenderungan terjadinya suatu efek media massa. Pemikiran terpenting dari teori ini bahwa
dalam masyarakat modern, audience menjadi tergantung pada media massa sebagai sumber
informasi bagi pengetahuan tentang, dan orientasi kepada, apa yang terjadi dalam
masyarakatnya. Kedua, berkaitan dengan apa yang dilakukan media yang pada dasarnya
melayani berbagai fungsi informasi (dalam Syaiful Rohim, 2009)
Media merupakan sarana publik yang seharusnya mampu menyajikan informasi yang benar,
komprehensif, dan cerdas. Media sebagai bagian dari komunikasi massa dituntut untuk selalu
akurat dan netral, fakta disampaikan dengan jujur dan tentunya dengan memperhatikan etika
jurnalisme. Begitu pula halnya dalam menyampaikan pendapat, bukan justru pendapat
disampaikan seakan fakta suatu realitas.
Media sebagai saluran juga harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan
kritik. Mampu mengangkat aspirasi publik, dan membuka akses keberbagai sumber informasi.
Media juga harus mampu mengfungsikan diri sebagai instrument pendidik bagi masyarakat,
sehingga masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan.
Menurut lasswell dan Wright (1975) ada empat fungsi Komunikasi Massa terhadap masyarakat,
sebagai berikut:
Pengawasan lingkungan
Fungsi ini merujuk pada pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai berbagai peristiwa
yang terjadi. Media massa menyebarkan segala kejadian dan peristiwa sehingga menjadi
informasi bagi khalayak. Kejadian dan peristiwa yang berkaitan dengan aspek-aspek sosial,
politik, ekonomi dan budaya akan selalu dilaporkan oleh media massa.
Penghubung antar bagian dalam masyarakat
Setiap sajian berita yang menyangkut hidup orang banyak, akan menjadi stimuli bagi khalayak
untuk memberikan tanggapan dan mengenalkan antara masyarakat satu dengan masyarakat
lainnya.
Sosialisai atau pewarisan nilai-nilai
Fungsi ini merujuk pada upaya transmisi dan pendidikan nilai-nilai serta norma-norma dari satu
generasi kepada generasi yang berikutnya, atau dari satu kelompok masyarakat terhadap para
anggota kelompok yang baru.
Hiburan
Fungsi hiburan merujuk upaya-upaya komunikatif yang bertujuan untuk memberikan hiburan
pada khalayak luas (dalam Yasir, 2009).
Melihat fungsi dari Komunikasi Massa diatas, maka pada pandangan kritis muncul satu
pertanyaan sederhana “apakah media mampu melakukan fungsinya tanpa intervensi dari
pemilik media?”.
Pesatnya perkembangan media massa saat ini, telah merubah media menjadi institusi yang
menjanjikan secara ekonomi bagi para pengusaha. Berbicara institusi secara ekonomi, tentunya
tidak akan lepas dari istilah pasar, produksi, barang, jasa dan keuntungan. Pasar media
tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan pasar lainya. Tentunya media mampu
memproduksi barang berupa informasi atau tayangan yang menarik. Sementara jasa yang
ditawarkan adalah media sebagai saluran yang menghubungkan para pengiklan dengan
masyarakat yang menkonsumsi media tersebut.
Tetapi tidak sedikit media memberikan informasi atau tayangan mainstream. Tidak jarang pula
bertentangan dengan etika jurnalisme, media dan penyiaran, hal ini dilakukan semata mata
untuk kepentingan ekonomi. Televisi swasta selalu berupaya untuk meningkatkan rating dan
menarik pengiklan sebanyak mungkin, dengan kata lain televisi swasta Indonesia akan
berlomba lomba untuk mengejar keuntungan secara ekonomi dibandingkan kepentingan publik.
Marxisme klasik memandang media sebagai alat bantu dari kelas yang dominan dan sebuah
untuk para kapitalis menunjukkan ketertarikan mereka dalam menghasilkan keuntungan. Media
menyebarkan ideologi dari dorongan yang berkuasa dalam masyarakat dan dengan demikian
menindas golongan-golongan tertentu (dalam Stephen W Littlejohn dan Karen A Foss, 2009).
Media tidak saja mendapat tekanan secara ekonomi, tetapi juga secara politik dari pemilik
media. Ketika pemilik media adalah tokoh politik, maka akan muncul kecenderungan untuk
menggunakan kekuatan media sebagai alat untuk mancapai tujuan politiknya. Hal ini jelas
sudah mengesampingkan hak masyarakat untuk menerima informasi dan tayangan yang jujur
dan memuat kebenaran.
Lihat saja TV One dan ANTV yang tergabung dalam Bakrie Group milik Abu Rizal Bakrie yang
juga Ketua Umum partai Golkar (Partai Golongan Karya). Kedua stasiun Televisi ini tidak
sungkan-sungkan menyampaikan informasi pencitraan politik Abu Rizal Bakrie. Begitu pula
halnya dengan Metro TV dan Media Indonesia yang bernaung dibawah Group Media Indonesia.
Media massa milik Surya Paloh ini seakan akan tidak ingin ketinggalan untuk memberikan
informasi dan pencitraan politik Partai Nasdem (Partai Nasional Demokrat) yang juga diketuai
oleh Surya Paloh.
Dan bukan hal yang aneh apabila pemilik media adalah tokoh yang pro pemerintah, sudah
dapat dipastikan media yang dimilikinya akan memberikan informasi dan tayangan yang juga
pro terhadap pemerintah. Hal ini bisa dilihat pada media lokal seperti Riau Pos. Koran harian
pagi milik Rida K Liamsi ini bersedia memberikan dua belas halaman khusus dari empat puluh
delapan halaman, sebagai sarana informasi mengenai kegiatan pemerintah Provinsi Riau (yang
mungkin lebih tepat dengan sebutan pencitraan).
Kondisi ini tentunya bertolak belakang dengan televisi yang dimiliki oleh Republik ini, lihat saja
Televisi Republik Indonesia selaku Lembaga Penyiaran Publik. Bisa dikatakan tidak mampu
memberikan contoh yang baik untuk televisi-televisi swasta. Bahkan tayangannya cenderung
membosankan dan mungkin saat ini sebagian masyarakat sudah tidak lagi melihatnya. Belum
lagi masalah intern pada LPP ini, TVRI belum mampu menyelesaikan permasalahannya pada
tataran manajemen yang tentunya sangat berpengaruh terhadap produksi televisi ini.
Seharusnya kondisi ini menjadi perhatian dari pemilik media dan masyarakat, tetapi juga
menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk mengatur regulasi media di Indonesia.
Bukankah media massa merupakan bagian dari demokrasi? Ketika media massa tidak lagi
mampu sebagai institusi ideal dalam menyampaikan informasi dan sudah menjadi media alat
bagi sang pemilik, hal ini tentunya akan terus merusak jalannya demokratisasi direpublik ini.
Media memiliki kekuatan yang besar dalam menyampaikan informasi dan tayangannya, akan
tetapi sangat lemah terhadap tekanan dari pemilik media. Dan kondisi ini hanyalah sebagian
kecil bentuk intervensi pemilik media dilihat dari kacamata ekonomi politik dan media.
4. Penutup
Media merupakan sarana publik yang seharusnya mampu menyajikan informasi yang benar,
komprehensif, dan cerdas. Media sebagai bagian dari komunikasi massa dituntut untuk selalu
akurat dan netral, fakta disampaikan dengan jujur dan tentunya dengan memperhatikan etika
jurnalisme.
Kepemilikan beberapa media oleh korporasi ini sangat tidak sehat dalam iklim demokrasi
Indonesia. Konglomerasi juga bentuk lain dari monopoli terhadap informasi dan monopoli
frekuensi yang seharusnya menjadi hak publik.
Fenomena konglomerasi media saat ini tentunya telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia.
Tetapi regulasi mengenai kepemilikan media saat ini masih memiliki banyak kelemahan.
Sehingga tidak mengalami perubahan yang berarti bagi pemilik media-media massa Indonesia.
Selain menghadirkan regulasi mengenai kepemilikan media massa yang berpihak kepada
masyarakat. Berharap pemerintah Indonesia mampu menempatkan orang-orang yang ber-
kompeten dibidangnya, untuk menuju Indonesia yang lebih baik dimasa mendatang.
5. Referensi
Rohim, Syaiful. 2009. Teori Komunikasi. Rineka Cipta, Jakarta
Littlejhon, Stepen W, Foss, Karen A. 2009. Teori Komunikasi, Salemba Humanika, Jakarta
Yasir. 2009. Pengantar Ilmu Komunikasi, Wita Irzani, Pekanbaru
10. Media mengontrol pemerintah
Analisis Media Indonesia Menggunakan
Perspektif Marxist dan Pluralist
Diposting oleh cityofevil • Di: Tugas Kuliah Fikom
June172014
Sistem media Indonesia sebenarnya menganut sistem demokrasi yang artinya media diberikan
kebebasan, namun masih ada kontrol dari pemerintah. tapi pada kenyataannya media Indoneisa jika di
amati secara teliti, akan ada berapa ciri media berdasarkan Marxist dan Pluralist. Dibawah ini akan
menganalisis media Indonesia berdasarkan perspektif Marxist dan perspektif Pluralist. Sebelum
menganalisis media indonesia, alangkah lebih baiknya jika dibahasa terlebih dahulu apa itu perspektif
Marxist, dan apa Perspektif Pluralist.
Perspektif Pluralist.
Ciri-ciri atau asumsi dari perspektif pluralist
1. Media memberikan informasi bagi publik untuk bertindak.
2. Media dapat mengontrol pemerintah dan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat karena
dianggap sebagai institusi independen.
3. Khalayak dianggap memiliki kehendak untuk menentukan berita sesuai dengan kebutuhan
mereka.
4. Media memberikan sarana agar debat publik bisa terjadi di situ.
5. Media merupakan institusi independen yang bebas dari campurtangan pemerintah
Analisis Media Berdasarkan Pluralist.
Setelah Indonesia reformasi, media massa diberikan kebebasan dalam menampilkan berita, dalam artian
media boleh menyajikan berita-berita baik itu dari aspirasi masyarakat atau hasil liputan media itu
sendiri. Berita yang di tayangkan sangat beragam ada yang mengkritisi pemerintah ada juga berita yang
sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya berita ekonomi, sosial dan budaya. Namun
berita tersebut masih mempunyai etika yang harus dipatuhi.
Sekarang masyarakat dapat dengan mudah menyuarakan aspirasi mereka atau hanya sekedar
memberikan pandangannya kepada pemerintah dan masyarakat luas. Dengan meluasnya jaringan
internet, menimbulkan semakin banyak media-media bercirikan/beraliran pluralistik. Ciri-ciri media
pluralistik itu sendiri sudah saya jelaskan diatas. Salahsatu media yang menganut kebebasan adalah
media berita online sebut saja Kompassiana, detikcom, kaskus, blogger. Dengan adanya media tersebut
masyarakat dengan mudah menulis dan meng-share tulisannya ke publik. Dengan fakta seperti ini, ada
sebagian media indonesia yang menganut pluralistik.
Perspektif Marxist
Ciri-ciri atau Asumsi Perspektif Marxist
1. Media massa dimiliki oleh orang-orang atau kelompok-kelompok borjuis.
2. Media dijalankan hanya semata-mata untuk kepentingan kaum borjuis
3. Media tidak memberikan akses kepada mereka yang yang memiliki pandangan politis
berlawanan
4. Media dianggap sebagai pertarungan ideologi antar kelas
5. Kontrol media sangat monopoli oleh para kaum borjuis
Analisis media berdasarkan Marxist.
Pada umunya seluruh media yang ada di Indonesia baik itu media cetak atau elektronik masing-masing
menyuarakan bahwa media tersebut independent. Namun pada kenyataan masih ada media yang
dikuasai/dibeli oleh individu untuk kepentingan pribadinya. Misalnya pada media Televisi, sekarang
banyak sekali pengusaha-pengusaha yang berlomba-lomba mendirikan media televisi. Motif dari
mendirikan media tersebut, mereka agar dapat dengan mudah menginformasikan pemikirannya (bisa
negatif/positif) kepada audiens atau khalayak. Dibawah ini beberapa media televisi yang dimilik oleh
perseorangan
Hary Tanoesoedibjopemilik Media MNC group (RCTI, Global, MNC, dll)
Aburizal Bakripemilik media televis TVONE
Surya Palohpemilik media televisi METROTV
Chairul Tanjungpemilik media televisi TRANS7 dan TRANSTV
Dengan semakin banyaknya televisi yang dimiliki oleh individu, maka kemungkinan akan mengarah ke
media Marxist yang ciri-cirinya sudah saya sebutkan diatas. Dengan kenyataan seperti ini maka semakin
jelas bahwa media di indonesia tidak sepuhnya independent. Karena televisi sekarang selain sebagai
motif ekonomi, juga sebagai tempat bertarungnya pengaruh oleh para pengusaha (mungkin kaum
borjuis)
Yang paling menyimpang adalah media tersebut sudah jauh melenceng dari prinsip media itu sendiri.
seperti televisi menayangkan berita-berita yang isinya hanya memintingkan kepentingan golongan
tertentu saja contohnya saat pemilu banyak sekali ditemukan kampanye-kampanye gelap. Seharusnya
media merupakan tempat untuk menampungnya aspirasi-aspira masyarakat.
Mengutip seperlunya dari
http://sharkiedick.wordpress.com/2010/03/10/studi-media-perspektif-pluralis-dan-perspektif-marxis/
(diakses: 23 Mei 2014, 06:34)
http://cityofevil.heck.in/analisis-media-indonesia-menggunakan-per.xhtml
Perspektif Sosiologis Dalam Media
Ada dua perspektif sosiologis dalam media, yaitu:
1. Pluralis-Liberalis
2. Marxist-Kritis
Adapun asumsi Pluralis adalah sebagai berikut:
1. Masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang bersama merealisasikan kepentingan
mereka sebelum ditentukan pemerintah. Keragaman yang terbentuk pun seimbang dan
tidak timpang sebelah. Contohnya masyarakat Jawa yang sangat menjujung tradisi atau
budaya Jawa mereka.
2. Semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengungkapkan keinginan
mereka. Tidak ada dominasi ataupun pembatasan dari kelompok lain.
3. Pemerintah hanya mengkoordinasikan warga supaya sejahtera. Tugas pemerintah hanya
mengatur supaya kesehatan warga terjamin, warga mendapat makanan yang cukup setiap
harinya, dan warga dapat hidup layak. Pemerintah disini bersifat netral.
4. Politik terbebas dari ekonomi. Kaya dan miskin sama di hadapan hukum.
5. Pelaksanaan kekuasaan selalu nyata / transparan.
Menurut Curran and Gurevitch (1982), asumsi pluralis di atas memunculkan asumsi-asumsi
media, yaitu:
1. Media menolong atau member kesempatan kepada semua orang utnuk menyuarakan
pendapat mereka di dalam sebuah forum atau debat.
2. Media memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dari warga negara untuk
melakukan suatu tindakan.
3. Media dianggap independen atau terbebas dari ekonomi dan pemerintah.
4. Media dapat mengontrol pemerintah dan berbagai kelompok kepentingan yang ada di
suatu negara.
5. Informasi hanya dianggap sebagai pengetahuan saja, bukan hasil konstruksi model
komunikasi.
6. Organisasi media dilihat sebagai sistem organisasi yang terkait dan menikmati otonomi
yang mereka miliki dari negara, parpol, dan kelompok-kelompok penekan yang
melembaga.
7. Kalangan elit manajerial merupakan kelompok professional media yang dianggap
mempunyai kebebasan untuk menentukan suatu hal.
8. Khalayak dianggap mampu untuk melihat manipulasi media. Bukan khalayak yang
menerima mentah-mentah hal-hal apa saja yang disajikan oleh media.
Model Pluralis
Contoh dari interest group adalah pengusaha, pengiklan, stake holder
Audience adalah kelompok yang memiliki kepentingan dan kepentinganya tersebut
terpenuhi / sasaran dari suatu program. Contoh audience dari tayangan Sinchan adalah
anak-anak ataupun siapa saja yang menonton tayangan tersebut.
Sedangkan public adalah pihak luar yang turut mempunyai kepentingan tertentu.
Contohnya dari tayangan sinchan adalah pemerhati anak-anak yang turut mengkritik
tayangan Sinchan yang dianggap tidak mendidik bagi anak-anak.
Pressure group adalah kelompok yang mampu menekan media dan seringkali berkaitan
dengan politik, contohnya adalah FPI, keluarga Cendana, dll
Media dilihat sebagai area kompetisi kelompok dan kepentingan isu-isu tertentu, secara
relative bersifat otonomi.
Pandangan Marxist
Produksi materi turut mempengaruhi produksi mental, keduanya saling mempengaruhi. Pemilik
produksi materi pasti akan menguasai produksi mental juga.
Contoh: saat di sekolah dasar siswa diajarkan untuk selalu mendengarkan gurunya, bertindak
pasif (produksi materi). Akibatnya saat di perguruan tinggi ketika mahasiswa dituntut untuk
akftif, banyak dari mereka yang takut dan segan untuk mengungkapkan pendapatnya (produksi
mental).
Asumsi media menurut pandangan Marxis
1 Media massa dimiliki oleh kaum borjuis
2. Media melayani atau memenuhi kepentingan borjuis
3. Media mempromosikan kesadaran palsu
4. Akses media tertutup terhadap pada oposisi politik
5. Media dilihat sebagai bagian dari arena ideologis dari bermacam-macam
pandangan, walaupun dalam konteksnya didominasi kelas-kelas tertentu
6. Kontrol utama dikuasai oleh pemilik modal monopoli
7. Media professional disosialisasikan oleh budaya-budaya tertentu
8. Media dianggap sebagai suatu keseluruhan yang menyiarkan kerangka kerja sesuai dengan
kepentingan kelas yang dominan.
9. Audience bersifat pasif dan memiliki akses yang terbatas ke media.
3 Pendekatan Marxist ke media:
1. pendekatan strukturalis = penekanan pada “internal articulation” sistem media
2.pendekatan politik ekonomi = kekuatan media dilokasikan pada proses ekonomi yang
mendasari produksi media
3. pendekatan kulturalis = media memliki kekuatan penuh untuk menimbulkan kesadaran public
Perbedaan Pluralis dan Marxist
Pluralis Marxist
Masyarakat beragam, memiliki kekuasaan
yang setara satu sama lain, dan
bebas
terbentuk dari faktor-faktor
produksi dan ekonomi. Dan ada
kesenjangan antara yang kaya
dan yang miskin, oleh karena
itu ada kelompok yang dominan
dan didominasi sehingga tidak
ada kesetaraan kekuasaan.
media bebas, dapat diakses secara
kompetitif
tidak bebas karena dikuasai
kelompok dominan
pesan pesannya beragam karena
media bebas menentukan isu
mana yang mau ditampilkan
pesan tidak beragam karena
adanya dominasi kelompok
tertentu, akibatnya pesan
cenderung menyuarakan
kepentingan kelompok tersebut.
khalayak aktif, bebas memilih media
mana yang mereka butuhkan
pasif dan memiliki akses yang
terbatas
produksi kreatif, bebas, dan original terstandarisasi, terkontrol, dan
dirutinkan
efek Banyak, tapi tidak ada
konsistensi dan dtidak dapat
ditebak arahnya kemana,
seringkali tidak ada efek
Kuat dan disahkan aturan sosial
professional mandiri dan outonomous Adanya ilusi otonomi,
disosialisasikan dan
diinternalisasikan ke dalam
norma-norma dari suatu budaya
yang mendominasi.
https://merlynacamelia.wordpress.com/2010/03/07/perspektif-sosiologis-dalam-media-2/