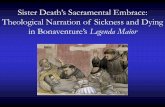Spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural - Spada ...
legenda malin kundang suatu kajian struktural lévi-strauss
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of legenda malin kundang suatu kajian struktural lévi-strauss
103
, Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra Volume 18 Nomor 2 Edisi Desember 2021 (103—120)
LEGENDA MALIN KUNDANGSUATU KAJIAN STRUKTURAL LÉVI-STRAUSS
The Legend of Malin Kundang, a Structural Study of Lévi-StraussDaratullaila Nasri1, Muchlis Awwali2
1Balai Bahasa Provinsi Sumatra BaratSimpang Alai Cupak Tangah, Pauh Limo, Pauh, Padang 25162
Hp: 081218186237Pos-el: [email protected]
2Jurusan Sastra Minangkabau, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas AndalasLimau Manis, Kecamatan Pauh, Padang 25163
Hp: 081374273461Pos-el: [email protected]
(Masuk: 22 Desember 2020, diterima: 30 November 2021)
Abstrak
Artikel “Legenda Malin Kundang suatu Kajian Struktural Lévi-Strauss” membicarakan makna yangterkandung dalam legenda Malin Kundang. Makna legenda tersebut dilihat dari sudut pandang strukturalyang digagas oleh Lévi-Strauss. Untuk menemukan makna dalam legenda tersebut penulis menggunakanmetode analisis struktural yang ditawarkan Lévi-Staruss tersebut. Dalam hal ini Lévi-Strauss” mengistilahkanmytheme (miteme) dan ceriteme. Dengan metode tersebut penulis mendapatkan hasil bahwa legendaMalin Kundang menggambarkan sistem kekerabatan yang menuju pada keluarga inti. Kemudian, merantauadalah salah satu konsep terpenting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Kesuksesan MalinKundang di perantauan menciptakan jarak antara anak dan ibunya (kaya dan miskin), dan bahkanmenghilangkan eksistensi sosok ibu dalam diri Malin Kundang. Pada puncaknya Malin Kundang terang-terangan tidak mengakui ibu kadungnya. Akibatnya, Malin Kundang dan kapalnya menjadi batu ataspengingkarannya itu. Kisah ini dapat menjawab kontradiksi atau dilemma yang terjadi tengah masyarakatMinangkabau, bahwa kesuksesan hidup lelaki Minang ditentukan bagaimana ia memperlakukan ibunya.Pengingkaran terhadap sosok dan peran ibu akan membawa malapetaka.Kata Kunci: Malin Kundang, strukturalisme Lévi-Strauss, matrilineal Minangkabau.
AbstractThe article “The Legend of Malin Kundang a Structural Study of Lévi-Strauss’’ discusses themeaning contained in the legend of Malin Kundang. The said meaning is seen from a structuralpoint of view initiated by Lévi-Strauss. In order to find the meaning, the writer uses a structuralanalysis method offered by Lévi-Staruss. In this case, Lévi-Strauss” uses the terms mythemeand ceriteme. Using this method, the writer unravels that the legend of Malin Kundangdescribes the kinship system that leads to the nuclear family. Then, wandering is one of themost important concepts in the life of Minangkabau people. Malin Kundang’s success overseascreated a distance between son and the mother (rich and poor). It even eliminated the existenceof a mother in Malin Kundang’s mind. In the end, Malin Kundang openly disowned his biologicalmother. As a result, Malin Kundang and his ship turned into stone for his denial. This storyanswers the contradiction or dilemma that occurs in Minangkabau society, that the successof a Minang man is determined by how he treats his mother. Denial of the figure and role ofthe mother could bring a disaster.Keywords: Malin Kundang, Lévi-Strauss structuralism, Minangkabau matrilineal.
104
PENDAHULUANCerita Malin Kundang merupakan
legenda perseorangan, yaitu mengenai seorangtokoh bernama Malin Kundang, yang dianggapbenar-benar terjadi oleh masyarakatpendukungnya (Danandjaja, 1986:73).Legenda ini bercerita tentang anak yangbernama Malin Kundang, yang semasa kecilnyahidup bersama ibunya karena ayahnya sudahmeninggal. Malin Kundang dan ibunya hidupdalam keadaan sangat miskin. Untukmemperbaiki dan meningkatkan taraf hidupmereka, Malin Kundang pergi merantau.Setelah berhasil di perantauan, Malin Kundangpulang bersama istrinya. Mendengar berita sianak pulang dari perantauan, ibunya menjemputke pelabuhan. Karena tua dan hidup melarat,Malin Kundang tidak mau mengakui perempuantua itu sebagai ibunya. Karena kecewa atasperlakuan Malin Kundang, ibunya lantas berdoakepada Tuhan agar memberikan hukumankepada Malin Kundang. Doa ibudiperkenankan Tuhan, maka kapal dan awakkapalnya dikutuk menjadi batu.
Legenda Malin Kundang cukup populerdi negeri ini, baik di tanah kelahirannya,Minangkabau maupun Indonesia. Kepopulerancerita itu tidak hanya dipahami orang-orangsebagai cerita rakyat, tetapi cerita tersebut jugadiapresiasi dengan baik oleh masyarakat. Halitu dibuktikan dengan banyaknya bermunculantulisan-tulisan yang diilhami legenda MalinKundang. Tulisan-tulisan tersebut lahir dalambentuk esai, cerpen, dan drama.
Beberapa karya atau tulisan yang diilhamilegenda Malin Kundang tersebut adalah sebagaiberikut. Karya-karya itu dapat dikelompokkanatas empat bagian, pertama dalam bentuk karyasastra, yaitu drama, cerpen, dan puisi. Kedua,dalam bentuk esai, dan ketiga dalam bentuktanggapan atas tanggapan. Keempat, karyailmiah berupa skripsi dan kertas kerja laporanpenelitian.
Dalam bentuk karya sastra, yaitu naskahdrama yang berjudul “Malin Kundang” (Hadi,1978). Dengan memanfaatkan formulakebudayaan Minangkabau dalam drama
tersebut, Hadi menggambarkan bahwa ‘sistemmatrilineal’ tidak lagi menjadi suatu yang idealbagi masyarakatnya (Nasri, 1999:25). Sistemmatrilineal telah menimbulkan konflik bagimasyarakat penganutnya sehingga Hadimenawarkan konsep patrilineal melaluikaryanya itu. Navis (1990:115—120) dalamcerpennya yang berjudul “Malin KundangIbunya Durhaka” berusaha memutar balikkanmitos yang dipahami masyarakat sebelumnya.Ketika anak berbuat kesalahan, diamendapatkan hukuman. Namun, ketika orangtua yang berbuat kesalahan, tidak ada hukumanuntuknya, sebagaimana yang dialami tokoh ibuMalin Kundang dalam cerpen tersebut.Bukankah segala perbuatan yang dilakukanseorang anak, orang tua juga andil di dalamnya.Inilah makna baru yang coba dihadirkan Naviskepada pembaca melalui cerpennya itu. Syah(1994) dalam cerpennya “Negeri MalinKundang”, mencoba menghadirkan realitasimajinasitif dalam dongeng menjadi realitasobjektif (Yusriwal, 2001:170). Lebih lanjutdijelaskan bahwa, Syah menganggap MalinKundang tersebut memang benar-benar adadalam realita kehidupan. Namun, yangditentangnya adalah pengkultusan terhadap diriMalin Kundang. Syah menggugat kepercayaanyang terdapat dalam masyarakat Aie Manihyang dianggapnya sebagai negeri MalinKundang, bahwa arwah Malin Kundang dapatmenyebabkan malapetaka jika tidak mengikutiajaran Malin Kundang. Bagi Syah tidakmungkin arwah orang yang sudah meninggaldapat berbuat sesuatu yang tidak dapatdilakukan manusia hidup. Semua kejadian dialam dapat terjadi hanya atas izin atau kehendakAllah. Arifin dalam cerpennya yang berjudul“Malin” (1992:232—234) menghadirkankonteks cerita yang lebih luas. Dalam hal iniArifin tidak lagi bersentuhan dengan budayaMinangkabau. Dia telah menembus bataskonteks sosial budaya tersebut sehingga ceritaitu bisa saja terjadi negeri-negeri yang ada diIndonesia, dan bahkan daerah-daerah lain yangada di dunia.
, Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra Volume 18 Nomor 2 Edisi Desember 2021 (103—120)
105
Dalam bentuk esai ada beberapa tulisanyang dapat dikemukakan di sini. Junusmenghasilkan beberapa tulisan mengenai MalinKundang tersebut. Di antaranya adalah sebagaiberikut: “Karya sastra Dilihat sebagaiDokumentasi Sosio Budaya” (Junus, 1986:5),“Fiksyen dan Legenda” (Junus, 1989:19),“Nilai Lampau Masa Kini” atau terjemahan daripast significance presence meaning (Junus,1989a), “Cerita Rakyat bukan Bacaan Kanak-Kanak Belaka” (Junus, 1981: 80—83),“Watak Cerekan dan Nama” (Junus,1993:114), dan “Malin Kundang MenantangMitosnya” (Junus, 1981:1—8). Razak (SinarHarapan, tt, hal VII) dengan judul tulisannya“”Tiada Maaf Bagimu” MalinKundang”(Razak, n.d.). Mohammad(1993:55—56) dengan judul tulisannya “PotretSeorang Penyair Muda sebagai Si MalinKundang”. Hadi (1985) menulis “Liem KhoonDoang”. Fadlillah menghasilkan dua tulisanmengenai Malin Kundang, yaitu “MalinKundang Kompleks: Sebuah Fenomenapsikologi dan Budaya (1997) dan ‘’MalinKundang”: sebagai Ideologi yang tersembunyi”(1998)
Bagian ketiga, tanggapan atas tanggapan,yang dimaksudkan tanggapan atas tanggapanadalah tulisan yang muncul karena menanggapitulisan atau karya yang lahir sebelumnya.Dengan kata lain, tanggapan pembaca ataskarya orang lain yang dibacanya sehingga diasendiri juga melahirkan sebuah karya baru.Dalam hal ini adalah tanggapan Soejanto danNadjib terhadap esai Mohammad yang berjudul“Potret Seorang penyair Muda sebagai Si MalinKundang”. Soejanto (1972) mengomentaridengan judul tulisannya “Esai Seorang Penyair”.Sementara itu, Nadjib (1975) menulis denganjudul “Sikap Malin Kundang Penyair: Idealisme,atau Topeng Keputusasaan”. Fadlillah (1983)muncul dengan tulisannya “Malin Kundang”Wisran hadi, Sebuah Kajian Intertekstualitas”.Tulisan tersebut merupakan kajian terhadapdrama Malin Kundang karya Wisran Hadi.Demikian juga halnya dengan Hidayat (2009)dalam penelitiannya yang berjudul “Malin
Kundang” Karya Wisran Hadi: SebuahPerbandingan”, dia mengkaji drama MalinKundang karya Wisran Hadi yangdiperbandingkannya dengan legenda MalinKundang.
Beberapa penelitian yang mengkajilegenda Malin Kundang di antaranya adalah“Cerita Malin Kundang: Suatu Tinjauan ResepsiSastra (Yusriwal, 1994 dan Nasri, 1999).Kemudian, “Legenda Malin Kundang:Manifestasi Sistem Matrilineal Minangkabau(Yusriwal, dkk 2001). Tulisan tersebutmenggunakan pendekan oral noetics yangdigagas oleh Oplan. Dalam konsep oralnoetics tersebut legenda (Malin Kundang)dapat dilihat sebagai perwujudan kebudayaanyang menggambarkan ide-ide, gagasan, nilai-nilai dan norma-norma suatu masyarakattertentu. Berdasarkan konsep tersebut Yusriwalmemanfaatkan data tulis dan data lisan sebagaiobjek penelitiannya. Data tulis adalah karyasastra yang terkait dengan cerita Malin Kundangdalam bentuk cerpen dan drama, sedangkandata lisan adalah hasil wawancara denganmasyarakat yang mengetahui legenda MalinKundang. Yusriwal menyimpulkan bahwasistem matrilinel Minangkabau dalam legendaMalin Kundang dikukuhkan, sedangkan dalamkarya sastra yang ditulis oleh penulisMinangkabau, sistem matrilineal dikriktik,dipertanyakan, dan bahkan dinafikan. Simpulanberikutnya, perbedaan itu terjadi karena waktupenciptaan sastra tulis dan lisan yang berbedasehingga menghasilkan interpretasi yangberbeda pula. Dari kedua simpulan tersebutYusriwal menyatakan bahwa cerita MalinKundang digunakan masyarakat Minangkabausebagai sarana untuk menyampaikan ide,gagasan, dan kritikan terhadap gejala sosialyang sedang berkembang ditengah kebudayaanmereka (2001:64). Selanjutnya, “Pola Lamadi dalam Sastra Modern: Malin Kundang didalam Salah Asuhan dan Sabai Nan Aluih didalam Sitti Nurbaya” (Tasai. Amran, 1994).
Dengan banyaknya orang-orang yangterilhami legenda Malin Kundang, hal itumenimbulkan pertanyaan dalam pikiran penulis,
Daratullaila Nasri, Muchlis Awwali: Legenda Malin Kundang Suatu Kajian Struktural Lévi-Strauss
106
apa makna di balik legenda Malin Kundangtersebut? Kalau sastra dikatakan memilikiketerkaitan dengan budaya, legenda MalinKundang sebagai sastra tentu memilikiketerkaitan dengan budaya pendukung legendatersebut. Dalam hal ini lagenda Malin Kundanghidup dalam sosio-budaya Minangkabau.Artinya, legenda Malin Kundang sebagai karyasastra merupakan manifestasi ide-ide, nilai-nilai,norma-norma dan sebagainya dari sebuahbudaya penganutnya. Untuk mengetahuiketerkaitan legenda Malin Kundang dengankebudayaan Minangkabau, penulis mencobamenerapkan teori struktural ala Lévi-Strauss.
Dalam hal ini penulis tidak melakukanpenelitian ke lapangan untuk pengambilan data,tetapi penulis memanfaatkan legenda MalinKundangan telah yang ditranskripsikan olehUdin (1996). Transkripsi tersebut merupakanhasil dari pertunjukan rebab. Cerita dalampertunjukan rebab biasanya disampaikan dalambentuk prosa lirik. Akan tetapi, legenda MalinKundang disampaikan dalam bentuk syair,kecuali pada awal dan akhir cerita memakaipantun (sebagai pembuka dan penutup cerita)(Udin, 1996:3).
Gaya penceritaan legenda Malin Kundangtersebut juga diluar kelaziman. Biasanya,legenda Malin Kundang disampaikan sepertipenceritaan dongeng-dongeng. Si pencerita bisasaja orang tua, guru mengaji dan sebagainya,yang bercerita kepada anak-anak atau murid-muridnya. Untuk dapat menceritakan legendatersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus.Dalam konteks pertunjukan rebab, barangkali,karena pencerita menggunakan media musikuntuk menyampaikan ceritanya, syair dalam halitu lebih tepat untuk mengisi melodinya.
Pemilihan data tersebut didasari atasbeberapa alasan. Pertama, legenda tersebutdisampaikan dalam bahasa Minangkabau. Halitu sangat membatu untuk memahami konteksbudaya yang menghidupi legenda tersebut.Kedua, penutur dari legenda tersebut adalahorang Minangkabau, sebagai pewaris darikebudayaan itu. Ketiga, campur tangan penurutcerita tidak terlalu dominan dalam teks. Dengan
kata lain, mungkin ada variasi dari ceritatersebut, tetapi tidak sampai menciptakanvarian baru.
LANDASAN TEORIPengertian mitos dalam pandangan
strukturalisme Lévi-Strauss tidak sama denganpengertian mitos yang ada dalam kajian mitologi(Ahimsa-Putra, 2006:77). Lebih lanjutdipaparkan Ahimsa-Putra, bahwa mitos dalampandangan Lévi-Strauss tidak mestidipertentangkan dengan sejarah atau kenyataankarena menurutnya perbedaan makna keduakonsep tersebut semakin sulit dipertahankan.Misalnya kata Ahimsa-Putra, sesuatu yangdianggap sejarah atau hal-hal yang dianggapbenar terjadi oleh masyarakat atau kelompoktertentu, ternyata bagi masyarakat lain haltersebut hanya dianggap sebagai dongeng yangtidak mesti diyakini kebenarannya. Mitosdalam hal ini tidak dianggap kisah yang sucilagi karena definisi ‘suci’ pun sudahproblematis. Maksudnya, sesuatu yangdianggap suci oleh masyarakat tertentu, ternyatadipandang biasa saja oleh masyarakat lain.
Jadi, mitos menurut Lévi-Strauss adalahpesan-pesan yang disampaikan melalui bahasaterhadap masyarakat (Ahimsa-Putra, 2006:80).Dalam pembacaan Taum (2021:1) tetangmitos—Lévi-Strauss —adalah sebagai bahasa,sebuah narasi yang sudah dituturkan untukdiketahui. Memasuki dunia mitos seolah-olahkita dihadapkan sebuah dunia yang kontradiktif,kata Taum. Selanjutnya dijelaskan Taum bahwadalam dunia mitos segala sesuatu dapat sajaterjadi, tidak ada logika, dan tidak adakontinuitas. Sifat-sifat apapun dapat diberikankepada subjek tertentu dan segala macam relasidimungkinkan. Ciri arbitrer itu menurut Taummuncul dalam semua mitos dari berbagaiwilayah di dunia. Oleh karena itu, menurutTaum hakikat mitos Lévi-Strauss adalah sebuahupaya untuk mencari pemecahan terhadapkontradiksi-kontradiksi empiris yang dihadapidan yang tidak dipahami oleh nalar manusia.
Salah satu wujud mitos adalah tuturan ataucerita yang disampaikan dari mulut ke mulut,
, Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra Volume 18 Nomor 2 Edisi Desember 2021 (103—120)
107
seperti legenda, dongeng, dan lain sebagainya.Dalam hal ini dongeng didefinisikan sebagaisebuah kisah yang tercipta dari hasil imajinasiatau khayalan manusia, walaupun unsur-unsurkhayalan tersebut berasal dari kehidupanmanusia sehari-hari (Ahimsa-Putra, 2006:77).Dalam penciptaan dongeng tersebut manusiamemiliki kebebasan yang mutlak, karena tidakada larangan bagi pembuat cerita menciptakandongeng apa pun.
Kebebasan dalam penciptaan itu dapatdilihat dalam cerita adanya manusia yangmenjadi batu akibat durhaka kepada orangtuanya (ibu), seperti kisah Malin Kundang diMinangkabau. Kisah si Malin Deman dengantujuh bidadari yang turun dari langit, mandi ditelaga, dan selendangnya dicuri oleh MalinDeman. Selain itu, kita juga pernah mendengardongeng dari nenek tentang si kancil yangberhasil menipu pak tani pemilik kebunmentimun. Kisah-kisah itu tidak tidak pernahkita temukan dalam kenyataan, kecuali hanyadalam dongengan.
Meskipun dongeng lahir atas dasar nalaratau khayal manusia, ia merupakan perwujudandari pergulatan pemikiran manusia dengan alamdan kebudayaan yang dihidupinya. Artinya,kisah-kisah dalam dongeng sekaligusmenggambarkan kebudayaan masyarakatpemilik dongeng tersebut. Oleh karena itu,dongeng atau legenda Malin Kundangmerupakan hasil penciptaan pencerita denganalam dan kebudayaannya.
Cerita Malin Kundang dituturkan dalambahasa Minangkabau. Bahasa Minangkabauadalah milik masyarakat Minangkabau. Dengandemikian, jika mitos adalah pesan-pesan yangdisampaikan melalui bahasa terhadapmasyarakatnya, Maka cerita Malin Kundangadalah milik masyarakat Minangkabau dansekaligus menyampaikan pesan kebudayaanyang ada di dalam masyarakat tersebut. Dalamcerita Malin Kundang tersebut, seolah-olah kitadihadapkan persoalan-persoalan yangberlawanan atau kontradiktif, seperti matrilineal
versus patrilineal, merantau versus berkumpul,dan sukses versus gagal. Persoalan itutergambar dari relasi-relasi antarindividu yangmerupakan tokoh-tokoh dalam peristiwa.
METODE PENELITIANMetode penelitian pada artikel ini
menggunakan analisis struktural yang di gagasoleh Lévi-Strauss. Menurut Lévi-Strauss setiapmitos dapat dipenggal menjadi segmen-segmenatau peristiwa-peristiwa (dalam Ahimsa-Putra,2006:102). Lebih lanjut dia menyatakan bahwasetiap segmen harus memperlihatkan relasi-relasi antarindividu yang merupakan tokoh-tokoh dalam peristiwa tersebut atau menunjukpada status-status dari individu-individu dalamcerita itu. Segmen itu diistilahkan mytheme(miteme) oleh Lévi-Strauss. Miteme dalamcerita dicari dalam bentuk kalimat.
Ceriteme adalah sebuah unit yangmengandung pengertian tertentu yang hanyadapat diketahui maknanya atau pengertiannyasetelah ditempatkan dalam hubungan denganceriteme-ceriteme yang lain (Ahimsa-Putra,2006:206). Lebih lanjut dijelaskan bahwaceriteme dapat ditemukan dalam rangkaiankalimat.
Untuk memudahkan dalam penganalisisandata, konsep miteme dan ceriteme yangditemukan dalam teks cerita dituliskan padasebuah kartu data. Kemudian, kartu data inilahyang dijadikan sebagai bahan analisis.
PEMBAHASANTerkait konsep miteme dan ceriteme
dalam legenda Malin Kundang, saya membagikisah tersebut atas tiga episode. Episode I: masaMalin Kundang di kampung. Episode II: masaMalin Kundang merantau. Episode III: masakembalinya Malin Kundang ke kampunghalamannya.
Masing-masing episode itu disajikandalam bentuk teks aslinya. Kemudian tekstersebut dijelaskan dalam bahasa Indonesiadalam bentuk parafrasa.
Daratullaila Nasri, Muchlis Awwali: Legenda Malin Kundang Suatu Kajian Struktural Lévi-Strauss
108
Episode I: Malin Kundang di Kampung(o ai)Nan kelok bakelok ujuang tali,ujuang tali pangabek paga,antah takabek antah tidak;(o) kelok bakelok ujuang nyanyi,ujuang nyanyi masuak ka kaba,antah ka dapek antah tidak (ai)
(o) kapa gulito dari tangah,sipotong di ateh batu;kaba curito nan didanga,bohong urang (o) tukang ‘ndak tau,
Curito kajadian di Ranah Minangiyo hikayat Malin Kundang,awak laia bapak bapulang,mande lah tingga jo’ rang bujang (o kawanai)
(o) sajak mulo (dik ai) bapaknyo mati,iduik mande mancari kayu api,anak dibao pagi-pagi,ka dalam rimbo (o) kayu dicari.
Pai pagi pulangnyo patang,kok untuang dapek bareh ‘gak sagantang,ka pambali lado jo bawang,co itu nasib mande Malin Kundang (tu ai).
Tampek tingganyo kalau dibilang,di pantai Pasisia kota Padang,di subarang aia di nan langang,iyo di kaki Gunuang Padang (ai)
Kalau daerah Ranah Minangurang lah tau jo curito si Malin Kundang,dari ketek sampai ka nan gadangdari pendek sampai (o) ka nan panjang.
Kalau dikana nasib diri,dapek patang abih lah pagi,jo bali kayu bareh di bali,karano mandeh tak balaki (lah mandekanduang ai)
(o) kalau dibilang si Malin Kundangdari ketek nyo lah sampai bujang,inyo mamandang patang-patangtampaklah kapa (o) baru datang (ai)
Kalau dibilang kapa kini,Malin bapikia sorang dirikok co iko nasib tiok aribia barangkek den dari nagari
Aso ilang duo tabilang,kok untuang barasaki di rantau urang,den jajak baliak tanah MInang,supayo kok lah tuo mande den sanang,
Lah bulek aia ka pambuluah,niek di ati marantau sabana sungguah,kini dakek isuak ka jauh,bacarai jo mande (o) ati ancua luluah(ai)
Hari malam duduak di pondok,lampu ketek taijok-ijok,mande dituruik dakok-dakok,mangecek jo mande manjalang lalok (ai)
Mande kanduang dangakan kini,lah tibo kapa padang tadi,mungkin kok kapa dari bugih,wakden taragak yo nak pai.
Mandanga kato anak kanduang,mande takajuik langsuang bamanuang,tasirok darah dalam jantuang,anak ka bacarai jo korong kampuang.
sudah itu mande manjawab pulo,manrantau Nak (ai) usang ang baco,Mande baransua tuo juo,musim pabilo ka basuo (nak ai)
(o) nak kanduang jan barangkek,Mande baransua juo gaek,sakik siapo (nak) ka maubek,nan bedo kok mati manggaletek,
Nan itu jangan mande rusuahkan,sakik jo mati usah ditakuikkan,kito ‘lah ada pajanjian,sarahkan diri kapado tuhan.
Di mande ado nan taraso,kini waang bansaik isuak kok kayo,jo mande kanduang waang kok lupo,itu di Mande (o) nan marusuah pulo (nakai)
Nan itu jangan Mande rusuahkan,palapehlah wakden nak bajalan,kok untuang rasaki dibari Tuhan,kepeang ka Mande capek den
kirimkan.Kalau co itu kato nak kanduang,Mande isinkan ang barangkek darikampuang,
, Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra Volume 18 Nomor 2 Edisi Desember 2021 (103—120)
109
bialah made tingga di kaki gunuang,anak jan lupo (o) jo Mande (lah) kanduang.(Udin, 1996:22—28).
Malin Kundang lahir ke dunia tanpakehadiran bapak karena sang bapak telahmeninggal dunia. Malin Kundang tinggal denganibunya. Dia dibesarkan oleh ibunya denganusaha mencari kayu. Ketika Malin Kundangmulai beranjak remaja, dia juga turut membantuibunya mencari kayu. Penghasilan mencari kayuitu sekadar mencukupi makan sehari-hari.
Menginjak usia mulai dewasa, MalinKundang sudah berpikir-pikir tentang keadaanhidupnya. Malin Kundang berkeinginan pergimerantau. Dia ingin mengubah nasibnya danibunya. Dia tidak mungkin bertahan dengankondisi hidup yang serba berkekurangan itu.
Malin Kundang mencoba menyampaikankeinginannya itu kepada ibunya. Dia tidakmendapatkan restu dari sang ibu untuk pergimerantau. Ibunya khawatir tidak dapat bertemudengan anaknya lagi karena usianya sudahsemakin tua. Kekhawatiran lain dari sang ibuadalah apabila Malin Kundang berhasil, diaakan lupa pada ibunya. Malin Kundang terusmembujuk ibunya dengan janji bahwa ia tidakakan melupakan ibunya jika sudah berhasil.
Pada akhirnya, ibu Malin Kundangmengizinkan anaknya pergi merantau. Sang ibuberharap, Malin Kundang berhasil di rantausehingga dapat menikah di kampung dan dapatpula mengganti rumah gubuknya dengan yanglebih baik.
Episode II: Masa Malin KundangMerantau
Malin lah tibo di kapa gadang,langsuang batanyo jo suaro tarang,mano nangkodo baru datang,lai kok buliah badan manumpang (ai).
Nak ka mano buyuang ka pai,kapa ka jauah ka tanah bugih,antah indak babaliak lagi,indakkoh ibo maninggakan nagari.
Kato dijawab samaso itu,waden ka pai indak ragu-ragu
karano lai pai jo angku,kok lai untuang (o) kampuang batamu
Kalau lah bulek, Yuang di dalam ati,rancak lah ang naik dari kinikarano kapa ampia pai,ka maninggakan nagari di ari kini (buyuangai)
...(o) kapa pai kampuang lah tingga (ai)Malin duduak jo ati susah,mande di pondok nan takanamungkin ka lamo (o) kampuang tingga(ai).
Malin bamanuang mamikiakan,karano awak balun makanlapa ka siapo dikatokan,awak di dalam palayaran
Sinan bamanuang si Malin Kundangnangkodo datang dari balakangmanolah buyuang baru datang,mangapo duduak bamanuang surang(nak ai).
Kato sampai Malin takajuik,lah kosong, Pak, rasonyo paruik,sia uran nan ka den turuk,wakden batanyo (o) maraso takuik
Kalau itu Buyuang manuangkan,marilah kito pai makannasi lah adoh urang sadiokan,jo Bapak Buyuang samo makan.
Sudah makan paruik lah kanyang,nangkodo batanyo ka rang bujang,siapo bana namo waang,urang maimbaukan supayo (lah) sanang(ai).
Nan kok itu Bapak tanyokan,Malin Kundang mande namokan,dari ketek dimabuak parasaian,mangko takana nak bajalan (ai)
Mandanga kato si Buyuang kini,nangkodo mandanga ibolah ati,taniek di ati nak mangasihi,disangko anak (o) kanduang sandiri.
Malin Kundang bakarajo sangaikrajinnyo,apo karajo inyo pun sato,bia manyapu jo manggiliang lado,
Daratullaila Nasri, Muchlis Awwali: Legenda Malin Kundang Suatu Kajian Struktural Lévi-Strauss
110
bapak mamandang batambah ibo....Abih maso (dek) baganti maso,Malin batambah pandai juo,nangkodo baransua tuo juo,kini Malin diangkek jadi nangkodo. (dik ai).
Ibaraik rajo nyo lah naiak nobaik,bapak lah jadi panasehaik (dik ai)Malin jadi nagkodo batambah hebat,badan gadang (o) tulang pun kuiak.
Bapak lah mulai (o) sakik (lah) sakik,rumik batenggang dalam raik,‘lah lamo badan disungkuik langik,mungkin badan (dik) ka jadi maik (lah ‘ndekanduang ai).
Dibuekkan Malin surek kuaso (dik ai),karano sakik batambah barek (lah)
juo,saluruah kakayaan Malin nan punyo,Ambun Sori tolong kawini pulo.
Surek sudah kato lah abih,surek ka Malin disarahkan kini,Malin manarimo sambia manangih,kapado bapak Malin (o) batarimo kasih.
…Tuan kanduang dangakan molah,jo siapo adiak ka tingga,ambo lah jaleh indak barayah,elok baok ambo jo kapa.
adik kanduang si Ambun Sori,usah adiak nan ka pai,ambo bujang adiak pun gadih,agak salah raso (o) dipandangi.
Tuan kanduang si Malin Kundang,Tuan disangko payuang gadang,tampek balinduang di paneh garangtampek bataduah di hujan gadang.
Sinan manjawab si Bujang Malin,iko nan kato di dalam batin,adik disangko sabagai kain,rancak kito sugiro kawin.
Kalau lah sungguah dalam ati,sasuai jo pasan bapak nan matikok nyampang isuak balakiusah nan lain nan ka dicari(Udin, 1996:32—56).
Malin Kundang pergi merantau hanyadengan bermodalkan keberanian. Diamemberanikan diri menemui pemilik kapal yangberlabuh di dekat kampungnya. Pemilik kapalitu adalah pedagang Bugis yang kaya raya.Pemili kapal dalam cerita disebut Nahkoda ataubapak Nahkoda. Dia menyampaikan maksuddan tujuannya kepada Nahkoda. Nahkoda punmenyambut baik kehadiran Malin Kundang.
Saat itu kapal berlayar ke Bugis. Dalamperjalanan Malin Kundang masih terlihat sedihsehingga dia lebih banyak bermenung danmenyendiri. Dia masih mengingat-ingat ibunyayang tinggal sendiri. Hal itu menjadi perhatianoleh Nahkoda. Nahkoda mencoba mendekatidan menanyai Malin Kundang. Malin Kundangpun menceritakan semua perihal dirinya, mulaidari masa kecilnya yang sudah ditinggal matioleh bapak sampai kemelaratan hidup yangdideritanya bersama ibunya. Kisah hidup MalinKundang itu menarik simpati Nahkodasehingga dia memperlakukannya sepertianaknya sendiri. Malin Kundang makindisayangi oleh Nahkoda karena dia rajinbekerja.
Ketika berlayar ke Bugis, Malin Kundangdibawa singgah oleh Nahkoda ke rumahnya.Malin Kundang bertemu dengan anakperempuanya, Ambun Sori. Kelak, MalinKundang menikah dengan Ambun Sori setelahayahnya meninggal. Pernikahan itu dilaksanakanatas wasiat ayah Ambun Sori. Dengan menikahiAmbun Sori, semua kekayaan Nahkodadiwariskan kepada Malin Kundang.Kehidupan Malin Kundang yang dahulu miskintelah berubah menjadi kaya raya.
Episode III: Malin Kundang Kembali keKampung
Adik kanduang (dik ai) si Ambun Soritaniek rasonyo di dalam ati,rindu jo mande patang pagi,rancak kito barangkek kini,
Kito manuju ka Ranah Minang,supayo ati ambo nak sanangnak kito liek Muaro Padang,
, Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra Volume 18 Nomor 2 Edisi Desember 2021 (103—120)
111
karano lah lamo ambo tak pulang.Kato sampai Amun sasuaisuah dibongka tali diungkai,dari tangah manuju pantai,aia mato darai-badarai
Dari malam baganti siang,ari siang Malin mamandang,lah nampak ruponyo Gunuang Padang,ati Malin Batambah mamang (lah tuan ai).
Ari nan sadang (dik ai) tangah (lah) ari,kapa marapek anyo lai,lah tapasang candonyo tali,nangkodo turun anyo (lah) lai.
Urang banyak lah mulai dating,maliek kappa nan paliang gadang,ado nan tau urang jo Malin Kundang,anak mande di kaki Gunuang Padang,
Malin dipandang sangaik gagahnyo,kapanyo gadang dipandang matobanyak lah galeh nan inyo bao,bininyo rancak inyo pun kayo (lah tuanai)
Urang nan tau (mak ai) barangkek daulu,manamui mande nan mancari kayu,anak jo mande supayo batamu,nak lapeh pulo ati nan rindu.
Sato tibo inyo bakatoo, Mande banrantilah bakarajo,anak Mande kini lah tibo,tampak bana di mato ambo.
Kato sampai Mande takajuik,laikoh waang indak salah sabuik,mangapokoh ambo bana waang japuik,nan bedo kok anak urang beko nan taturuik(lah buyuang)
Kato sampai Mande bajalanDituruik anak balahan badan,Di tangah jalan tangih ditahan,Rindu jo anak ka dilapehkan.
Satu tibo mande mamandanglah tampak rupo si Malin Kudang,daulu ketek kini lah gadang,mande tak lupo kapado waang(lah nak kanduang ai).
Dibilang Malin tagak jo bini,urang di pandang batambah rami,lah tampak pulo mande badiri,
ati di dalam barubah kini(Udin, 1996:54—62)
Karena sudah berhasil di rantau, MalinKundang berniat untuk melihat ibunya yangsudah lama ditinggalkannya. Dia mengutarakanniatnya itu kepada istrinya, Ambun Sori. AmbunSori pun menyetujuinya.
Malin Kundang mengarahkanpelayarannya ke Ranah Minang. Setelah kapalMalin Kundang sampai di Muaro Padang,semua orang berduyun-duyun melihatnya.Mereka sudah mengetahui bahwa kapaltersebut yang membawa Malin Kundang pergimerantau. Mereka meyakini bahwa MalinKundang masih bekerja di kapal itu. Ketikakapal tersebut telah di tepian dan melihat bahwaMalin Kundang bukanlah anak buah kapal lagi,tetapi dialah pemilik kapal itu. Malin Kundangdatang dengan segala kemegahan dan kekayaanyang dimilikinya. Semua itu disaksikan olehorang di pantai itu.
Namun, tidak demikian halnya dengan ibuMalin Kundang, dia mengetahui anaknya pulangsetelah diberitakan orang lain. Pada saat itu,ibu Malin Kundang sedang mencari kayu.Mendengar berita itu, ibu Malin Kundangtergopoh-gopoh menuju pantai. Sesampai disana, ibu Malin Kundang melihat anak danistrinya berdiri di kapal besar itu. Malin jugaMelihat ibunya yang sudah mendekati kapalnya.
Ketika itu, Malin Kundang melihat ibunyatidak ubahnya seperti pengemis di jalanan.Orang tua berpakaian sangat lusuh dengankondisi yang memprihatinkan. Melihat kondisisi ibu, Malin Kundang merasa malu. Dia malukepada istrinya. Malin Kundang telah menjadiorang kaya, mana mungkin dia memiliki ibusemiskin perempuan tua itu. Oleh karena itu,dia membentak ibunya ketika ibunya memanggildirinya. Malin Kundang mengatakan, “janganrang tuo batele-tele, ambo nan indak anakmande, barangkeklah kini sabalun denpaneh” (Udin, 1996:62) (jangan orang tuabertele-tele, saya bukan anak ibu, pergilahsekarang, sebelum saya marah).
Daratullaila Nasri, Muchlis Awwali: Legenda Malin Kundang Suatu Kajian Struktural Lévi-Strauss
112
Ibu Malin Kundang terkejut mendengarkata-kata anaknya. Dia menjawab dengan hatisedih, “O, Malin sadarlah kini, lupokohwaang jo janji, samaso dulu waang ka pai”(Udin, 1996:62), (O, Malin sadarlah, lupakahkamu dengan janji, ketika kamu akan pergi).
Sementara itu, Ambun Sori melihat sikapMalin Kundang yang berbeda dari biasanya, iapun berkata, “o Tuan, junjuangan ambo, kokiyo itu mande kito, mangapo Tuan sarupoiko” (Udin, 1996:62), (O Tuan, junjungan saya,jika ia itu ibu kita, mengapa Tuan berbuatseperti ini.
Malin Kundang menjawabnya denganperkataan yang sangat kasar, “itu nan bukanMande ambo, itu rang tua nan cilako,anjiang balai pauni muaro, ranca diusia darisiko” (Udin, 1996:62), (itu bukan ibu saya, ituorang tua yang celaka, ajing balai penghunimuara, lebih baik diusir dari sini).
Ibu Malin Kundang menangis mendengarperkataan anaknya. Dia pun berkata, “ondeh,nak kanduang rangkaian ati, nan Mandearok nak patang jo pagi, mangapo co ikokato waang kini” (Udin, 1996:64) (wahai, nakkandung rangkaian hati. Yang Bunda harappetang dan pagi, mengapa engkau berkataseperti ini).
Malin Kudang masih belum puasmembentak ibunya. Dia mendekati perempuantua itu dan memukulinya hingga terjatuh. Ketikaitu, ibu Malin Kundang masih sempat berkatadi tengah isak tangisnya, “ondeh,nakkanduang si Malin Kundang, dari ketek kinilah gadang, mangapo sampai (nak ai)Mande ang buang” (Udin, 1996:64), (wahai,nak kandung Malin Kundang, dari kecil kinitelah bujang, mengapa sampai Bunda kaubuang).
Malin Kundang tetap tidak berubah, diaberkata kepada ibunya, “Kau jangan banyakcurito, barangkeklah kau dari siko, anjiangtuo anjiang cilako, kok ndak barangkekambo talo” (Udin, 1996:64), (Kau janganbanyak cerita, berangkatlah kau dari sini, anjingtua anjing celaka, hamba pukul kalau tak pergi).
Setelah mendengar makian dari anaknya,ibu Malin Kundang pergi meninggalkan MalinKundang. Dia pergi menuju pondoknya dalamkeadaan bercucuran air mata. Sesampai dirumah, dia masih menyesali perbuatan anaknya.Dia mengadukan kesedihannya kepada yangMahakuasa. Dia bermohon kepada Tuhan agaranaknya diberi hukuman atas perbuatan yangtelah dilakukannya.
Malin Kundang pada saat itu sudah beradadi tengah lautan, tiba-tiba datang badai dangelombang besar. Semua yang ada dalam kapalitu sudah porak-poranda. Malin Kundang sadarbahwa malapetaka itu datang disebabkanperbuatannya. Untuk itu, dia memohon ampunkepada Tuhan atas kesalahannya itu. Namun,pintu tobat telah tertutup bagi Malin Kundang.Kapal dan awak kapalnya ditakdirkan Tuhanmenjadi batu di pantai Aia Manih, Padang.
Dari ketiga episode tersebut dapat dilihatbeberapa relasi yang muncul dalam cerita, yaiturelasi anak dengan ibu, anak buah denganmajikan, dan anak dengan ibu. Semua relasi itumemiliki makna yang berbeda-beda. Demikianjuga halnya dengan relasi anak dan ibu yangmuncul diawal dan akhir cerita, kedua relasi itumengandung makna yang berbeda.
1. Relasi antara Anak dengan Ibu (masaMalin Kundang di Kampung)
Masa Malin Kundang di kampungmelukiskan relasi antara anak dengan ibu.Dalam hal ini si anak memiliki keterikatan yangsangat kuat dengan ibu. Karena tidak lagimemiliki ayah, Malin Kundang hanyamengharapkan kasih sayang dan perhatian dariibunya.
Demikian pula dengan ibu Malin Kundang,dia juga mencurahkan semua perhatiannyakepada anak semata wayangnya itu. Katakundang pada nama Malin Kundang tersebutmerupakan salah satu bukti bahwa MalinKundang adalah anak yang disayangi dandimanjakan oleh ibunya. Kata kundang dalambahasa Minangkabau berarti ‘dibawa’ (ikutpergi ke mana-mana) (Usman, 2002:324).
, Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra Volume 18 Nomor 2 Edisi Desember 2021 (103—120)
113
Maka “Malin Kundang” dapat diartikan ‘Malinyang biasa dibawa ke mana saja oleh si ibu.Begitulah rasa sayang dan tanggung jawabseorang ibu sehingga dia sendiri tidak mauberjarak apalagi berpisah dengan anaknya. Siibu tidak ingin terjadi sesuatu dengan anaknya.Apa pun yang terbaik pasti dilakukan ibu untukanaknya.
Malin Kundang sebagai anak jugaberusaha menyenangkan hati ibunya. Dia patuhkepada ibunya. Dia juga tidak segan-seganmembantu ibunya mengumpulkan kayu api.Kayu itu dijual untuk kebutuhan hidup mereka.Tingkah laku dan sikapnya dalam bergaul jugamenyenangkan hati ibunya.
Kata malin pada nama Malin Kundangtersebut menunjukkan bahwa dia anak yangbaik dan dalam pergaulannya dihargaimasyarakat. ‘Malin’ bukan nama, tetapi gelaradat yang diberikan kepada laki-lakiMinangkabau yang telah berkeluarga. Katamalin itu berasal dari bahasa Arab mu’allimyang berarti ‘orang yang berilmu’ (Usman,2002:389). Dalam bahasa Minangkabau katatersebut dilafalkan malin yang mengandung artiorang yang memahami agama danmenjalankannya dengan baik. Berdasarkan, artidari nama Malin, maka cerita Malin Kundangberkembang setelah agama Islam berkembangdi Minangkabau.
Mengkaji nama Malin Kundang tersebut,barangkali ada benarnya apa yangdikemukakan oleh Sati (2008:29) bahwa“Malin Kundang” adalah gelar yang diberikanmasyarakat dilingkungannya. Sebagimanakebiasaan orang Minangkabau saat itu yangsuka memberi gelar atau julukan kepada orang-orang tertentu. Misalnya, orang yang jalannyapincang diberi gelar “si pengka’, orang yangmatanya rusak sebelah diberi gelar “si celek”,orang yang bibir atasnya belah diberi nama “sisumbing”.
Dari penjelasan tersebut dapat ditariksimpulan bahwa relasi anak dengan ibu dalamhal ini adalah semata-mata disatukan oleh kasihsayang. Artinya, dalam relasi tersebut tidakterlihat bahwa seseorang merasa lebih
dipentingkan daripada yang lain atau seseorangmerasa berkuasa atas kehidupan orang yangdikuasainya. Ibu Malin Kundang memangberkuasa atas diri anaknya, tetapi dia tidakmemiliki sifat menguasai dalam arti negatif. Diaberperan sebagai ibu yang mengayomi anaknyadengan sepenuh jiwa dan raganya. Si anak punmenunjukkan kepatuhannya terhadap ibu.
2. Relasi antara Anak Buah dengan IndukSemang (Masa Malin KundangMerantau)
Untuk dapat memahami relasi antara anakbuah dan induk semang, terlebih dahulu sayaperlu mengemukakan konsep merantau dalamkehidupan lelaki Minangkabau. Konsepmerantau tersebut berkaitan dengan dengankedudukan laki-laki dalam sistem kekerabatanmatrilineal. Pada masa dahulu, semenjak umur6—7 tahun laki-laki Minangkabau sudah harusmeninggalkan rumah dan hidup di surau (Naim,1984:277). Di rumah gadang tidak ada kamaruntuk anak laki-laki karena kamar-kamardiperuntukkan bagi saudaranya yangperempuan. Bagi anak laki-laki yang masihbertahan tidur di rumah gadang, biasanyamenjadi ejekan di kalangan teman-temannya.Dia dikatakan belum bercerai menyusu denganibunya.
Surau merupakan institusi sosial bagiorang Minangkabau. Di surau itu laki-lakiMinangkabau mendapatkan pendidikan danilmu pengetahuan. Di sana mereka diajarkanadat istiadat, nilai-nilai, dan norma-norma yangberlaku dalam masyarakat. Mereka jugadiajarkan ilmu bela diri dan pencak silat. Selainitu, jiwa mereka juga disentuh dengan seni,terutama seni sastra.
Hidup di surau mereka jalani sampaimenjelang usia menikah. Setelah menikahmereka tentu akan tinggal di rumah istrinya.Menikah bukan berarti laki-laki Minangkabautelah memiliki rumah. Hal ini menimbulkankonflik batin tersendiri baginya. Sebagaimanayang dinyatakan oleh Naim (1984:276) bahwakedudukan laki-laki Minangkabau serbaterkatung-katung antara dua rumah (rumah
Daratullaila Nasri, Muchlis Awwali: Legenda Malin Kundang Suatu Kajian Struktural Lévi-Strauss
114
ibunya dan rumah istrinya). Di rumah istrinyadia dianggap sebagai tamu (sumando). Diadihormati, tetapi tanpa hak dan kekuasaan.Kato (2005:62) menyebutkan bahwa posisisuami selalu merupakan masalah dalammasyarakat matrilineal. Dia diperlakukansebagai ‘penjantan’ untuk menyambungketurunan kelompok matrilineal istri, tetapi diajuga berada dalam posisi yang mungkinbersaing untuk berkuasa atas istri dan anak-anaknya dengan anggota-anggota lelaki darikelompok matrilineal istri. Lebih lanjut Katomenyatakan bahwa peranan suami kurangpenting dalam kehidupan istri dan anak-anaknya, antara lain karena makanan merekadijamin dan disediakan oleh paruik istri yangmenguasai tanah pusaka, sumber ekonomi yangutama. Sementara itu, di rumah ibunya didudukkan sebagai mamak, sebagai pengawalkeluarga, tetapi tanpa hak untuk menikmati hasilsawah ladang yang dapat dibawanya ke rumahistrinya. Hal itu menyebabkan laki-lakiMinangkabau merasa risih (Naim, 1984:276).
Demikian juga halnya dengan laki-lakiMinangkabau yang belum berumah tangga.Mereka tidak mungkin bertahan hidup di surauatau luntang-lantung di lepau-lepau. Jika merekatetap bertahan hidup di surau, orang-orangkampung biasanya memanggil dengan sebutanpakiah, namun jika waktunya dihabiskan dilepau-lepau maka orang-orang kampungmenyebutnya dengan parewa. Biasanya pakiahdan parewa kurang diminati untuk dinikahkandengan anak gadis dikampungnya. Karenasecara ekonomi kurang menjanjikan untukdapat hidup sejahtera. Oleh karena itu, sebagaianak muda, mereka tentu menginginkan masadepan yang lebih baik dan eksistensinya diakuidi tengah masyarakat.
Jalan keluar dari semua persoalan tersebutadalah merantau. Merantau bukan berartimigrasi. Menurut Naim (Naim, 1984:3)merantau mengandung makna (1) meninggalkankampung halaman, (2) dengan kemauan sendiri,(3) untuk jangka waktu yang lama atau tidak,(4) dengan tujuan mencari penghidupan,menuntut ilmu atau mencari pengalaman, (5)
biasanya untuk kembali pulang, dan (6)merantau adalah sebagai lembaga sosial yangmembudaya. Sementara itu, migrasi berartiperpindahan penduduk dari suatu tempat ketempat lain, belum tentu bermaksud untukpulang ke kampung asal.
Pergi merantau bukanlah pelarian dariikatan sosial. Merantau bagi laki-lakiMinangkabau merupakan suatu cara yangdianggap baik untuk melaksanakan tanggungjawabnya. Merantau dianggap sebagai realisasidari bentuk tanggung jawab terhadap keluarga,kaum, dan suku. Kebiasaan merantaudipandang oleh orang Minangkabau sebagaisatu cara untuk mengangkat harga diri, keluarga,dan kaumnya. Hal itu tercermin dari ungkapanadat berikut ini.
Karatau madang di huluBabuah babungo balunMarantau bujang dahuluDi kampuang paguno balun
(Keratau madang di huluBerbuah berbunga belumMerantau bujang dahuluDi kampung perguna belum
Ungkapan adat di atas mengisyaratkanbahwa laki-laki Minangkabau harus bermanfaatbagi keluarga dan masyarakat. Jika belum,sebaiknya dia meninggalkan kampung untukbelajar dan menimba pengalaman di daerahrantau. Merantau diharapkan kembali kekampung, agar bermanfaat bagi masyarakat dikampung, baik secara langsung maupun tidaklangsung. Prinsipnya bahwa sesuatu yang datangdari rantau harus bermanfaat bagi anggotakeluarga khususnya dan masyarakat padaumumnya.
Salah satu makna yang tersirat dari konsepmerantau itu adalah mencari kekayaan, yanghasilnya nanti akan dibawa pulang. Suatu halyang berlaku umum apabila keberhasilanseseorang di rantau diukur masyarakat denganbanyaknya harta yang dibawa oleh si perantaudari tempat perantauannya. Demikian juga
, Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra Volume 18 Nomor 2 Edisi Desember 2021 (103—120)
115
dengan keberadaan si perantau akan diakui ditengah masyarakat apabila kekayaan yang diamilikinya dapat dimanfaatkan untuk kepentinganmasyarakat.
Jika si perantau pulang dengan tanganhampa, dia dianggap gagal dan dicemoohkanoleh masyarakat. Hal itulah yang menyebabkanorang Minangkabau enggan untuk pulang kekampung halaman setelah merantau sekian lamakarena ia merasa tidak memiliki apa-apa untukdipamerkan nantinya di kampung halaman.Bahkan, ada yang memutuskan untuk tidakpulang sama sekali. Mereka seperti hilangditelan bumi perantauan. Orang Minangkabaumengistilahkan dengan marantau Cino. Sepertiorang Cina yang pergi meninggalkan kampunghalamannya dan tidak pernah kembali ketempat asalnya, serta memutuskan hubungandengan tanah leluhurnya. Hal itu juga terjadipada perantau Minangkabau yang memutuskanhubungan dengan kampung halamannya.
Sikap perantau yang seperti itu hanyaterjadi pada segelintir orang. Sejalan denganitu, Abdullah (dalam Hadler, 2010:xxvii) jugamemberikan tanggapan mengenai polamerantau orang Minangkabau bahwa, pertama,tindakan merantau yang dilakukan denganmaksud menetap di tempat yang dituju, dankedua, merantau sebagai keharusan, tetapisekaligus diidealkan bagi anak muda yangmenjelang dewasa.
Kemudian, Graves (2007:38)mengatakan bahwa merantau merupakan suatupetualangan pengalaman dan geografis. Orangnagari aktif mengunjungi rantau; dengan sadaria memutuskan untuk meninggalkan rumah dansanak keluarga untuk mencoba merantau danmengadu nasib. Meskipun berada di rantauorang, tetapi hubungan dengan kampunghalaman tidaklah terputus.
Konsep merantau di atas dapatdihubungkan dengan peristiwa merantau yangdialami Malin Kundang. Malin Kundang pergimerantau karena faktor ekonomi. Kesusahanhidup membuatnya harus pergi danmeninggalkan ibu yang dicintai. Tujuan MalinKundang pergi merantau adalah untuk
mengubah hidupnya sendiri dan ibunya ke arahyang lebih baik.
Hal pertama yang dilakukan MalinKundang adalah mencari orang atau induksemang yang dapat ditempatinya. Induksemang atau majikan bagi perantauMinangkabau memiliki makna tersendiri. Halitu tergambar dalam idiomnya yang berbunyi,
kalau anak pai marantauinduak cari sanak pun cariiduak samang cari dahulu”(kalau anak pergi merantauIbu cari saudara pun cariInduk semang cari dahulu)
Mengapa ajaran adat Minangkabaumenganjurkan perantaunya mencari induksemang? Dalam pandangan orangMinangkabau, induk semang adalah orang yangmampu dari segi ekonomi. Dia juga dipandangsebagai orang yang sukses dan sudah banyakpengalaman. Sikap dan perilakunya menjadianutan dan contoh bagi orang lain. Oleh karenaitu, induk semang menjadi tempatan pertamabagi perantau menjelang si perantau bisa hidupmandiri.
Malin Kundang diterima Nahkodamenjadi anak buah di kapalnya. Diamemperlihatkan kesungguhan hati dalambekerja. Dia tidak suka menyia-nyiakan waktu.Hari-harinya diisinya dengan bekerja danbekerja. Di samping giat bekerja, MalinKundang juga dapat dipercaya.
Pengabdian Malin Kundang sebagai anakbuah terhadap induk semangnya bukan berartisemata-mata untuk disayangi dan disenangioleh majikan. Akan tetapi, lebih dari itu, yaituuntuk mendapatkan pengetahuan dan wawasanyang dimiliki tuannya itu. Jika induk semangnyaseorang pedagang, dia berusaha menyerapkepandaian berdagang dari induk semangtersebut. Kepandaian tersebut sangatdibutuhkan ketika dia harus menjadi pribadiyang mandiri.
Hal itu dapat dibuktikan Malin Kundangketika Nahkoda sudah meninggal. Malin
Daratullaila Nasri, Muchlis Awwali: Legenda Malin Kundang Suatu Kajian Struktural Lévi-Strauss
116
Kundang diwasiatkan Nahkoda untukmenjalankan usaha perdagangan tersebut danmenikahi putrinya. Di sini dapat dilihatkemampuan Malin Kundang berdagang. Diadapat menyamai dan bahkan bisa melebihikepandaian induk semangnya.
Dengan demikian, dapat dinyatakanbahwa relasi antara anak buah dengan induksemang adalah atas dasar kepentingan, terutamakepentingan dari segi ekonomi. Malin Kundangmembutuhkan pekerjaan agar hidupnya lebihbaik, sedangkan Nahkoda membutuhkantenaga kerja untuk menjalankan usahanya.Hubungan tersebut bukan disebabkan kasihsayang di antara keduanya, sebagaimana kasihsayang seorang ibu dan ayah terhadap anaknyadan demikian sebaliknya, kasih sayang seoranganak terhadap ayah dan ibunya. Akan tetapi,hubungan itu dapat diistilahkan dengan istilahperdagangan, yaitu ‘untung dan rugi’. Yangnamanya berdagang tidak ada orang yang maurugi dan maunya selalu untung.
Hal itu tercermin dalam kisah MalinKundang ketika Nahkoda memberikan wasiathartanya kepada Malin Kundang. Hartatersebut tidak diberikan Nahkoda begitu saja,tetapi diharus memenuhi yang disyaratkannya,yaitu menikahi putrinya. Jika Nahkoda sudahmenganggap Malin Kundang sebagai anaknya,tentu dia tidak perlu meminta Malin Kundangmenikahi putrinya. Harta itu pun tentu diberikandengan cuma-cuma. Malin Kundang punmemenuhi wasiat itu karena harta. Harta itu telahlama menjadi impiannya.
3. Relasi antara anak dan ibu (masa MalinKundang Kembali ke Kampung)
Perantauan yang dilakukan MalinKundang telah menghantarkan dirinya menjadiorang yang sukses. Dia telah memiliki kekayaanyang selama ini menjadi impiannya.Pengembaraannya untuk menjadi orang yangsukses telah memisahkan dia dan ibunya denganbegitu lama. Pulang ke kampung halamanadalah sebuah kerinduan bagi Malin Kundang.Ketika kesuksesan telah diraihnya, dia punkembali pulang. Dia pulang untuk menemuiperempuan yang telah melahirkannya.
Pertemuan mereka di pelabuhan membuatsegalanya berubah. Malin Kundang tidakmengakui perempuan tua itu sebagai ibunya. Iamalu mempunyai ibu yang miskin, sedangkandia telah menjadi orang kaya raya. Ibu dan MalinKundang berada pada kelas sosial yangberbeda. Malin Kundang berada di posisi kelassosial yang tinggi, sedangkan si ibu masihberada pada kelas sosial yang paling rendah.Mengakui perempuan tua itu sebagai ibunyaberarti menurunkan derajatnya.
Dengan tidak mengakui si ibu, berartiMalin Kundang telah memutuskan hubunganantara dirinya dengan ibunya. Kasih sayangseorang ibu yang telah membesarkannya telahdikhianatinya. Sebagai anak Minangkabau,Malin Kundang telah menghilangkan raso jopareso (rasa dan periksa) yang seharusnyamenjadi pegangan hidupnya. Bagi orangMinangkabau, orang yang telah kehilangan rasojo pareso adalah orang yang tidak dianggapatau tidak dipentingkan dalam masyarakat.
Navis (1984:72) menjelaskan bahwamakna raso itu adalah kemampuan untukmenimbang sesuatu yang terasa sakit pada dirisendiri akan terasa sakit pula pada orang lain.Begitu pula juga sebaliknya, segala sesuatu yangterasa enak bagi diri sendiri hendaknyamembuat orang lain merasa suka juga. Dalamhal rasa senang, ukuran yang dipakai adalahlamak dek awak, katuju dek urang (enakbagi kita, suka bagi orang). Artinya, setiapkesenangan yang kita dapatkan hendaknyadisukai oleh orang lain, setidaknya jangansampai mengganggu orang lain. Jangan sampaiukuran tersebut menjadi lamak dek awak,tambuah ciek lai (enak bagi kita, bolehditambah). Artinya, kesenangan yang kitadapatkan hanya untuk diri sendiri, sementaraorang lain tidak perlu kita pedulikan, apakahikut senang atau tidak.
Pareso, menurut Navis (1984:72),memiliki makna kemampuan untuk menimbangbahwa apa yang kita lakukan sesuai dengankepatutan dan hukum yang berlaku. Ukuranpareso itu memakai nilai alur jo patuik (alurdan patut). Hal itu dimaksudkan agar kita selalumemeriksa masalah menurut alur yang lazim,
, Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra Volume 18 Nomor 2 Edisi Desember 2021 (103—120)
117
tetapi tetap mempertimbangkannya denganrasa kepantasan atau kepatutan. Secarasederhana dapat dikatakan bahwa segalasesuatunya diperiksa dengan hati nurani sendiri.
Pemakaian raso jo pareso harusseimbang. Raso mempertimbangkan pareso,demikian juga sebaliknya pareso harusmengendalikan raso. Hal ini terjadi dalam waktuyang bersamaan. Ilyas (2003:28)menggambarkan pemakaian raso jo pareso itusesuai dengan falsafah adat alam Minangkabaudengan peribahasa raso dibao naiak, paresodibao turun (rasa dibawa naik, periksa dibawaturun). Idiom tersebut mengandung makna,yaitu apa yang dipikirkan bila hendakdilaksanakan haruslah diuji kebenarannyadengan perasaan, dan dirasakan biladilaksanakan diuji dengan pikiran. Apabilamenurut rasa sudah pantas dilakukan,sedangkan pemikiran tidak cocok, makasebaiknya ditunda atau tidak dilakukan samasekali, begitu juga sebaliknya, kalau menurutrasa tidak pantas, tetapi menurut pemikirancocok.
Dengan hilangnya raso jo pareso dalamdiri Malin Kundang, maka tidak ada lagihubungan antara Malin Kundang, sebagai anakdengan ibunya. dia telah menjadi individu yangbebas. Akan tetapi, kebebasan itu tidakdikehendaki oleh ibunya. Dia tidak inginanaknya semakin jauh tersesat. Oleh karenaitu, si ibu menyerahkan semua persoalannyakepada Tuhan untuk menentukan nasibanaknya.
SIMPULANDari analisis di atas dapat disimpulkan
relasi anak dan ibu (masa di kampung)melahirkan hubungan kasih sayang di antarakeduanya. Ikatan anak dan ibu semakin kuatkarena tidak ada sosok lain seperti ayah,mamak dan saudara perempuan ibu sebagaitempat berbagai kasih sayang. Ayah MalinKundang dalam teks dikisahkan telahmeninggal semasa dia kecil. Jika ayah tidak ada,mamak dan saudara perempuan ibu memilikiperan penting untuk membersamai kehidupan
Malin Kundang dan Ibunya. Akan tetapi, halitu tidak tergambar dalam teks. Ketiadaan peranmamak dan juga saudara perempuan ibumelahirkan tafsiran bahwa cerita MalinKundang menggambarkan kondisi masyarakatMinangkabau menuju keluarga Inti.
Relasi yang terbangun antara anak buah(Malin Kundang) dan induk semang padaakhirnya melahirkan hubungan darah karenaadanya pernikahan antara Malin Kundangdengan Ambun Sori, anak induk semang.Dengan adanya induk semang ini lah, MalinKundang sebagai laki-laki Minang mengujinyalinya menjalani kehidupan merantau.Perantauan yang dijalani Malin Kundangberhasil membawanya pada puncakkesuksesan.
Episode terakhir, relasi Malin Kundangdan ibunya (kembali ke kampung setelahberhasil di rantau) memperlihatkan bahwa telahterjadi “pengkhianatan” Malin Kundangterhadap ibunya. Malin Kundang memungkirijanjinya kepada ibu kandungnya. Tidak hanyaitu, ia juga tidak mengakui lagi ibu kandungnyasendiri. Akibatnya, ia menjadi batu ataspengkhianatannya.
Dari relasi tersebut dapat disimpulkansebuah klarifikasi “kode budaya” dari ceritaMalin Kundang, yaitu bahwa cerita inimenjawab sebuah kontradiksi (dilemma) didalam masyarakat Minangkabau tetang nasihatadatnya, yakni kesuksesan hidup lelaki Minangditentukan bagaimana dia memperlakukanibunya. Pengingkaran terhadap sosok danperan ibu akan membawa malapetaka. Ibuadalah sosok yang harus dihormati dandimuliakan, sebagaimana diajarkan dalamajaran Islam yang menjadi landasan bagikebudayaan Minangkabau tersebut.
DAFTAR PUSTAKAAhimsa-Putra, H. S. (2006). Strukturalisme
Lévi-Strauss Mitos dan Karya Sastra.Kepel Press.
Arifin, S. (1992). “Malin.” Horizon, 7, 232—234.
Daratullaila Nasri, Muchlis Awwali: Legenda Malin Kundang Suatu Kajian Struktural Lévi-Strauss
118
Danandjaja, J. (1986). Folklor Indonesia:Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-lain.Grafiti Pers.
Fadlillah. (1983, April). “Malin KundangWisran Hadi Sebuah KajianIntertekstualitas.” Singgalang.
Fadlillah. (1997, January). “Malin KundangKompleks: Sebuah Fenomena Psikologidan Budaya.”. Singgalang.
Fadlillah. (1998, January). “Malin Kundang:Sebagai Ideologi yang Tersembuyi”.Singgalang.
Graves, E. E. (2007). Asal Usul EliteMinangkabau Modern ResponsTerhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX. Yayasan Obor Indonesia.
Hadi, W. (1978). “Malin Kundang” (naskahdrama).
Hadi, W. (1985). “Liem Khoon Doang”.Horizon.
Hadler, J. (2010). Sengketa Tiada PutusMatriakat, Reformisme Islam, danKolonial. Freedom Institute.
Hidayat, H. N. (2009). “Malin Kundang”Karya Wisran Hadi: SebuahPerbandingan”.
Ilyas, A. (2003). Nan Empat. Dialektika,Logika, Sistematika AlamTerkembang. Lembaga Kerapatan Adat.
Junus, U. (1981). Mitos dan Komunikasi.Sinar Harapan.
Junus, U. (1986). Sosiologi Sastra:Persoalan Teori dan Metode. DewanBahasa dan Pustaka KementerianPendidikan Malaysia.
Junus, U. (1989a). Catatan Si MalinKundang: Antologi Esai. DewanBahasa dan Pustaka KementerianPendidikan Malaysia.
Junus, U. (1989b). Fiksyen dan SejarahSuatu Dialog. Dewan Bahasa danPustaka Kementerian PendidikanMalaysia.
Junus, U. (1993). Dongeng tetang Cerita.Dewan Bahasa dan Pustaka KementerianPendidikan Malaysia.
Kato, T. (2005). Adat Minangkabau danmerantau: dalam Perspektif Sejarah.Balai Pustaka.
Mohammad, G. (1993). “Potret SeorangPenyair Muda sebagai Si MalinKundang” dalam Kesusastraan danKekuasaan. Pustaka Karya Grafikatama.
Nadjib, emha A. (1975, September).“Idealisme atau Topeng Keputusasaan?”Kompas.
Naim, M. (1984). Merantau: Pola MigrasiSuku Minangkabau. Gadjah MadaUniversity Press.
Nasri, D. (1999). “Cerita Malin Kundang:Suatu Tinjauan Resepsi Sastra”.Universitas Andalas.
Navis, A. A. (1984). Alam Terkembang JadiGuru: Adan dan KebudayaanMinangkabau. Grafiti Press.
Navis, A. A. (1990). Bianglala: KumpulanCerita Pendek. Pustaka KaryaGrafikatama.
Razak, A. (n.d.). Tiada Maaf Bagimu”: MalinKundang”. Sinar Harapan, VII.
Sati, D. S. . (2008). Malin Kundang danRancak di Labuah. Ar-Rahman.
Soejanto, H. (1972, July). “Esai SeorangPenyair”. Kompas.
Syah, I. (1994, March). “Negeri MalinKundang” (cerpen). Singgalang.
Tasai. Amran. (1994). “Pola Lama di dalamSastra Modern: Malin Kundang didalam Salah Asuhan dan Sabai NanAluih di dalam Sitti Nurbaya”.Universitas Indonesia.
Taum, Yoseph Yapi. 2014. “Teori-Teori AnalisisSastra Lisan: Strukturalisme Levi Straus”.Diakses pada 15 November 2021 darihttps://www.scribd.com/doc/205132324/Strukturalisme-Levi-Strauss.
Udin, S. (1996). Rebab Pesisir Selatan: MalinKundang. Yayasan Obor Indonesia.
Usman, A. K. (2002). Kamus Umum BahasaMinangkabau-Indonesia. AnggrekMedia.
, Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra Volume 18 Nomor 2 Edisi Desember 2021 (103—120)
119
Yusriwal. (1994). “Cerita Malin Kundang:Suatu Tinjauan Resepsi Sastra”.
Yusriwal, dkk. (2001). “Legenda MalinKundang Manisfestasi dari SistemMatrilineal Minangkabau”.
Daratullaila Nasri, Muchlis Awwali: Legenda Malin Kundang Suatu Kajian Struktural Lévi-Strauss