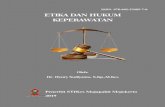LAPORAN TUGAS AKHIR - Repository STIKES BHM
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of LAPORAN TUGAS AKHIR - Repository STIKES BHM
ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “T” MASA KEHAMILAN
TRIMESTER III, PERSALINAN, NIFAS, NEONATUS DAN
KB PASCASALIN DI PMB SITI ROHMANI, S.ST
DAGANGAN KABUPATEN MADIUN
LAPORAN TUGAS AKHIR
Oleh :
KARISMA HAYU ISLAMI
NIM.201701020
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN
TAHUN 2020
i
ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “T” MASA KEHAMILAN
TRIMESTER lll, PERSALINAN, NIFAS, NEONATUS DAN
KB PASCASALIN DI PMB SITI ROHMANI, S.ST
DAGANGAN KABUPATEN MADIUN
LAPORAN TUGAS AKHIR
Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Ahli Madya
Kebidanan pada Program Studi DIII Kebidanan STIKES Bhakti Husada Mulia
Madiun
Oleh:
KARISMA HAYU ISLAMI
NIM. 201701020
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN
TAHUN 2020
ii
LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN TUGAS AKHIR INI TELAH DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN PADA UJIAN SIDANG
LAPORAN TUGAS AKHIR
TANGGAL 17 JULI 2020
ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “T” MASA KEHAMILAN
TRIMESTER III, PERSALINAN, NIFAS, NEONATUS DAN
KB PASCASALIN DI PMB SITI ROHMANI, S.ST
DAGANGAN KABUPATEN MADIUN
Oleh:
KARISMA HAYU ISLAMI
NIM.201701020
Menyetujui,
Pembimbing I
Lucia Ani Kristanti, S.Si.T., M.Kes
NIS : 20090060
Menyetujui,
Pembimbing II
Assasih Villasari, S.Si.T
NIS : 20080050
iii
LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN TUGAS AKHIR INI TELAH DIPERTAHANKAN
DIDEPAN TIM PENGUJI UJIAN SIDANG LAPORAN TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN STIKES
BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN
PADA TANGGAL 7 AGUSTUS 2020
ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “T” MASA KEHAMILAN
TRIMESTER III, PERSALINAN, NIFAS, NEONATUS DAN
KB PASCASALIN DI PMB SITI ROHMANI, S.ST
DAGANGAN KABUPATEN MADIUN
Oleh:
KARISMA HAYU ISLAMI
NIM. 201701020
MENGESAHKAN
TIM PENGUJI TANDA TANGAN
Ketua Penguji : Mertisa Dwi Klevina, S.ST., M.Kes ……………………
Penguji I : Lucia Ani Kristanti, S.Si.T,. M.Kes ……………………
Penguji II : Assasih Villasari, S.Si.T ……………………
Mengesahkan,
Ketua STIKES
Zaenal Abidin, SKM. M.Kes (Epid)
NIS. 20160130
Mengetahui,
Ketua Prodi DIII Kebidanan
Assasih Villasari, S.Si.T
NIS.20080050
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas semua berkat dan rahmatNya
sehingga dapat terselesaikannya Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Asuhan
Kebidanan Pada Ny ”T” Masa Kehamilan Trimester III, Persalinan, Nifas,
Neonatus Dan KB Pascasalin di PMB Siti Rohmani,S.ST” sebagai salah satu
syarat menyelesaikan pendidikan Ahli Madya Kebidanan pada Program Studi
Kebidanan STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun.
Dalam hal ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak,
karena itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih
kepada :
1. Zaenal Abidin, SKM.,M.Kes (Epid), selaku Ketua STIKES Bhakti Husada
Mulia Madiun, yang telah memberikan kesempatan menyusun Laporan Tugas
Akhir ini.
2. Assasih Villasari, S.Si.T, selaku Ketua Program Studi Kebidanan STIKES
Bhakti Husada Mulia Madiun sekaligus selaku pembimbing II, yang telah
memberikan memberikan kesempatan dalam menyusun Laporan Tugas Akhir
ini.
3. Lucia Ani Kristanti, S.Si.T, M.Kes selaku pembimbing I yang telah
memberikan bimbingan sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat
terselesaikan.
4. Mertisa Dwi Klevina, S.ST.,M.Kes, selaku ketua penguji yang telah
memberikan kesempatan menyusun Laporan Tugas Akhir ini.
5. Siti Rohmani, S.ST yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan
penyusunan Laporan Tugas Akhir di PMB Siti Rohmani, S.ST.
6. Ny. “T” atas kerjasamanya yang baik.
7. Alm.Bapak, Ibu, kakak dan seluruh keluarga atas cinta, dukungan moral,
materil dan doa yang selalu diberikan sehingga Laporan Tugas Akhir ini
selesai pada waktunya.
v
8. Rekan seangkatan dan pihak-pihak terkait yang telah membantu dalam
penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan pahala atas segala amal
baik yang telah diberikan dan semoga Laporan Tugas Akhir ini berguna bagi
semua pihak yang memanfaatkan.
Madiun, Agustus 2020
Penulis
vi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... iii
KATA PENGANTAR ...................................................................................... iv
DAFTAR ISI ..................................................................................................... vi
DAFTAR TABEL ............................................................................................. x
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ xi
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xii
DAFTAR SINGKATAN ................................................................................ xiii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1
A. Latar Belakang ........................................................................................ 1
B. Pembatasan Masalah ............................................................................... 8
C. Tujuan ...................................................................................................... 8
D. Ruang Lingkup ...................................................................................... 10
E. Manfaat ................................................................................................... 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................... 12
A. Kehamilan .............................................................................................. 12
1. Konsep Dasar Kehamilan ................................................................. 12
a. Pengertian ........................................................................................ 12
b. Fisiologi Kehamilan ........................................................................ 12
c. Tanda-Tanda Kehamilan ................................................................. 17
d. Perubahan Fisiologi Pada Kehamilan ............................................. 22
e. Perubahan Psikologis Pada Kehamilan ........................................... 27
f. Kebutuhan Dasar Ibu Hamil ............................................................ 31
g. Ketidaknyamanan Ibu Hamil .......................................................... 39
h. Tanda Bahaya Pada Ibu Hamil ....................................................... 48
i. Antenatal Care (ANC) ..................................................................... 50
j. Continuity Of Care (COC) ............................................................... 61
vii
k. KSPR (Kartu Score Poedji Rochjati) .............................................. 62
l. Indeks Massa Tubuh (IMT) ............................................................. 70
m. Menentukan Tafsiran Persalinan ................................................... 71
2. Konsep Dasar Asuhan Kebidanan Kehamilan ............................... 71
B. Persalinan ............................................................................................... 83
1. Konsep Dasar Persalinan .................................................................. 83
a. Pengertian ........................................................................................ 83
b. Sebab Terjadinya Persalinan ........................................................... 84
c. Macam-Macam Persalinan .............................................................. 86
d. Faktor yang Mempengaruhi Persalinan .......................................... 86
e. Perubahan Fisiologi Pada Ibu Bersalin ........................................... 91
f. Perubahan Psikologi Pada Ibu Bersalin ........................................... 99
g. Tahapan Persalinan ....................................................................... 101
h. Kebutuhan Dasar Selama Persalinan ............................................ 103
i. Tanda dan Gejala Inpartu ............................................................... 104
j. Mekanisme Persalinan ................................................................... 105
k. Tanda Bahaya Persalinan .............................................................. 109
l. Penapisan Ibu Bersalin Normal ..................................................... 109
m. Lima Benang Merah Persalinan ................................................... 110
n. Partograf ........................................................................................ 115
2. Konsep Dasar Asuhan Kebidanan Persalinan Normal ................ 126
C. Nifas ...................................................................................................... 148
1. Konsep Dasar Masa Nifas ............................................................... 148
a. Pengertian ...................................................................................... 148
b. Tahapan Masa Nifas ..................................................................... 149
c. Perubahan Fisiologis Masa Nifas .................................................. 149
d. Perubahan Psikologis Masa Nifas ................................................. 158
e. Kebutuhan Dasar Masa Nifas........................................................ 160
f. Menyusui dan Laktasi .................................................................... 167
g. Komplikasi pada Masa Nifas dan Penanganannya ....................... 175
h. Tanda Bahaya Masa Nifas ............................................................ 180
viii
i. Kunjungan Nifas ............................................................................ 181
j. Tujuan Asuhan Masa Nifas............................................................ 182
k. Standart Asuhan Nifas .................................................................. 183
2. Konsep Dasar Asuhan Kebidanan Masa Nifas ............................. 184
D. Neonatus ............................................................................................... 194
1. Konsep Dasar Neonatus .................................................................. 194
a. Pengertian ...................................................................................... 194
b. Adaptasi Fisiologi Neonatus ......................................................... 195
c. Ciri-Ciri Bayi Baru Lahir Normal ................................................. 206
d. Klasifikasi Neonatus ..................................................................... 207
e. Reflek ............................................................................................ 208
f. Perawatan Segera Setelah Bayi Lahir ............................................ 211
g. APGAR Score ............................................................................... 212
h. Neonatus Beresiko Tinggi............................................................. 214
i. Tanda Bahaya Neonatus ................................................................ 215
j. Kunjungan Neonatus...................................................................... 215
k. Imunisasi ....................................................................................... 216
2. Konsep Dasar Asuhan Kebidanan Neonatus ................................ 220
E. Keluarga Berencana Pascasalin ......................................................... 229
1. Konsep Dasar KB ............................................................................ 229
a. Pengertian ...................................................................................... 229
b. Pentingnya KB Pascasalin ............................................................ 229
c. Macam-Macam KB Pascasalin ..................................................... 230
d. Tujuan Program KB ...................................................................... 266
e. Ruang Lingkup Program KB ........................................................ 267
2. Konsep Dasar Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana ............. 268
BAB III ASUHAN KEBIDANAN ............................................................... 275
A. Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil .................................................. 275
B. Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin .............................................. 286
C. Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas.................................................... 298
D. Asuhan Kebidanan Pada Neonatus ................................................... 306
ix
E. Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana .......................................... 316
BAB IV PEMBAHASAN .............................................................................. 324
A. Kehamilan ............................................................................................ 324
B. Persalinan ............................................................................................. 325
C. Nifas ...................................................................................................... 327
D. Neonatus ............................................................................................... 328
E. Keluarga Berencana (KB) ................................................................... 330
BAB V PENUTUP ......................................................................................... 332
A. Kesimpulan .......................................................................................... 332
B. Saran ..................................................................................................... 333
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 335
LAMPIRAN ................................................................................................... 338
x
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Perkembangan Fungsi Organ Janin ............................................. 17
Tabel 2.2 Diagnosis Kehamilan ................................................................... 22
Tabel 2.3 Tujuan ANC ................................................................................. 52
Tabel 2.4 TFU MC. Donald ......................................................................... 54
Tabel 2.5 IMT .............................................................................................. 71
Tabel 2.6 Penurunan kepala janin menurut sistem perlimaan ................... 106
Tabel 2.7 Penapisan Ibu Bersalin ............................................................... 109
Tabel 2.8 Ukuran uterus setelah persalinan ............................................... 150
Tabel 2.9 Lokia .......................................................................................... 152
Tabel 2.10 Perbandingan angka kecukupan energi dan zat gizi wanita
dewasa dan tambahannya untuk ibu hamil dan menyusui ......... 163
Tabel 2.11 Komposisi ASI ........................................................................... 175
Tabel 2.12 Penilaian bayi dengan metode APGAR score ........................... 213
Tabel 2.13 Pengamatan BBL dengan APGAR score ................................... 213
Tabel 2.14 Analisis APGAR score .............................................................. 214
Tabel 2.15 Jadwal Imunisasi ........................................................................ 220
Tabel 2.16 Kondisi yang perlu dipertimbangkan bagi pengguna alat
kontrasepsi kondom ................................................................... 235
Tabel 2.17 Penanganan efek samping spermisida ....................................... 238
Tabel 2.18 Penanganan efek samping diafragma ........................................ 243
xi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Pemeriksaan leopold ............................................................... 55
Gambar 2.2 Kartu Score Poedji Rochjati .................................................... 70
Gambar 2.3 Mekanisme persalinan normal .............................................. 108
Gambar 2.4 Derajat laserasi perineum ...................................................... 122
Gambar 2.5 Partograf bagian depan .......................................................... 124
Gambar 2.6 Partograf bagian belakang ..................................................... 125
Gambar 2.7 Mekanisme kehilangan panas pada BBL .............................. 199
Gambar 2.8 IUD Copper T ....................................................................... 250
Gambar 2.9 IUD Nova T........................................................................... 250
Gambar 2.10 IUD Mirena ........................................................................... 251
xii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian ............................................................... 338
Lampiran 2 Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian ..................... 340
Lampiran 3 Lembar Permohonan ............................................................. 341
Lampiran 4 Lembar Informed Consent .................................................... 342
Lampiran 5 Identitas Keluarga ................................................................. 343
Lampiran 6 Catatan Kesehatan Ibu Hamil................................................ 344
Lampiran 7 KSPR ..................................................................................... 345
Lampiran 8 Stiker P4K ............................................................................. 346
Lampiran 9 Menyambut Persalinan .......................................................... 347
Lampiran 10 Penapisan Ibu Bersalin .......................................................... 348
Lampiran 11 Partograf ................................................................................ 349
Lampiran 12 Catatan Kesehatan Ibu Bersalin, Nifas dan BBL .................. 351
Lampiran 13 Surat Keterangan Lahir ......................................................... 352
Lampiran 14 Catatan Kesehatan Ibu Nifas ................................................ 353
Lampiran 15 Catatan Kesehatan Bayi Baru Lahir ...................................... 354
Lampiran 16 Catatan Imunisasi .................................................................. 355
Lampiran 17 Kartu Menuju Sehat .............................................................. 356
Lampiran 18 Grafik Berat Badan Menurut PB/TB..................................... 357
Lampiran 19 Grafik Lingkar Kepala .......................................................... 358
Lampiran 20 Daftar Penapisan KB Hormonal dan Non Hormonal ............ 359
Lampiran 21 Informed Consent KB ........................................................... 360
Lampiran 22 Kartu KB ............................................................................... 361
Lampiran 23 Dokumentasi ......................................................................... 362
Lampiran 24 Lembar Konsultasi Bidan ...................................................... 363
Lampiran 25 Lembar Konsultasi Dosen ..................................................... 364
Lampiran 26 Referensi Data AKI dan AKB Menurut WHO ..................... 365
xiii
DAFTAR SINGKATAN
AGO : Ada Gawat Obstetri
AKB : Angka Kematian Bayi
AKI : Angka Kematian Ibu
AMP : Audit Maternal Perinatal
ANC : Ante Natal Care
APGO : Ada Potensi Gawat Obstetri
ASI : Air Susu Ibu
BAB : Buang Air Kecil
BAK : Buang Air Kecil
BB : Berat Badan
BBL : Bayi Baru Lahir
BBLR : Berat Badan Lahir Rendah
BCG : Ballcillus Calmette Guerin
COC : Continuity Of Care
CPD : Cepalo Pelvic Dispropotion
DJJ : Detak Jantung Janin
DPT : Difteri, Pertusis, Tetanus
DT : Difteri Toksoid
Hb : Hemoglobin
hCG : Chorionic Gonadotropin
HPHT : Hari Pertama Haid Terakhir
IM : Intramuskular
IMD : Inisiasi Menyusu Dini
IMT : Indeks Masa Tubuh
INC : Intra Natal Care
IPM : Indeks Pembangunan
JKN : Jaminan Kesehatan Nasional
K1 : Kunjungan ibu hamil pertama kali
K4 : Kunjungan ibu hamil minimal 4 kali
xiv
KB : Keluarga Berencana
Kf : Kunjungan nifas
KH : Kelahiran Hidup
KIA : Kesehatan Ibu dan Anak
KIE : Komunikasi, Informasi dan Edukasi
KN : Kunjungan Neonatal
KRR : Kehamilan Resiko Rendah
KRST : Kehamilan Resiko Sangat Tinggi
KRT : Kehamilan Resiko Tinggi
KSPR : Kartu Skor Poedji Rochjati
KTP : Kartu Tanda Penduduk
LiLA : Lingakr Lengan Atas
MDGs : Millennium Development Goals
MMR : Measles, Mumps and Rubella
No.RMK : Nomor Rekam Medik
OPV : Oral Poli Vaccine
P4K : Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi
Pf : Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas
kesehatan
PMB : Praktik Bidan Mandiri
Pn : Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
PNC : Post Natal Care
PPI : Program Pengembangan Imunisasi
Renstra : Rencana Strategi
RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDGs : Sustainable Development Goals
SPM : Standar Pelayanan Minimal
SSP : SIstem Saraf Pusat
TB : Tinggi Badan
TFU : Tinggi Fundus Uteri
TP : Taksiran Persalinan
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan keluarga dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan
keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Selain
lingkungan yang sehat, kondisi kesehatan dari tiap anggota keluarga sendiri
juga merupakan salah satu syarat dari keluarga yang berkualitas.Keluarga
sebagai komponen dari masyarakat berperan signifikan dalam mempengaruhi
status kesehatan. Ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu
mendapatkan prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, karena ibu
dan anak merupakan kelompok yang rentan. Hal ini terkait dengan fase
kehamilan, persalinan dan nifas pada ibu dan fase tumbuh kembang pada
anak. Hal ini yang menjadi alasan pentingnya upaya kesehatan ibu dan anak
menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia (Kemenkes
RI, 2019b). Keberhasilan upaya kesehatan ibu dan anak dapat dilihat dari
indikator angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB)
(Kemenkes RI, 2018b).
AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan
nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau
pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau
terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2019b). Sedangkan,
angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan
keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir
sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal
dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan
yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit
penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat
AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang
sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah
khususnya di bidang kesehatan (Badan Pusat Statistik, 2012).
2
Menurut World Health Organization (WHO) Kematian ibu sangat
tinggi. Pada tahun 2017 sekitar 295.000 wanita meninggal selama dan setelah
kehamilan dan persalinan. Kematian ibu dapat disebabkan karena komplikasi
selama dan setelah kehamilan dan persalinan. Sedangkan Angka Kematian
Bayi (AKB) pada tahun 2018 sebesar 2,5 juta jiwa (WHO, 2019).
Target Millenium Development Goals (MDG’s) 2015 yaitu menekan
Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup dan
Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup. Program
terbaru dari WHO sebagai acuan AKI dan AKB Indonesia yaitu Sustainable
Development Goals (SDG’s) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
sebagai pengganti MDG’s yang berakhir pada tahun 2015 dalam menurunkan
angka kematian ibu (AKI) secara global hingga kurang dari 70 per 100.000
kelahiran hidup ditahun 2030, dan AKB sebesar 12 per 1.000 kelahiran hidup.
Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia secara umum terjadi penurunan
kematian ibu selama periode 1991-2015 dari 390 menjadi 305 per 100.000
kelahiran hidup. Walaupun terjadi kecenderungan penurunan angka kematian
ibu, namun tidak berhasil mencapai target MDGs yang harus dicapai yaitu
sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Sedangkan
Angka Kematian Bayi (AKB) menurut hasil Survei Demografi dan Kesehatan
Indonesia (SDKI) tahun 2017 sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup
(Kemenkes RI, 2019). Sehingga dapat disimpulkan bahwa AKI dan AKB di
Indonesia belum memenuhi target SDG’s.
Sedangkan AKI di Jawa Timur pada tahun 2018 mencapai 91,45 per
100.000 kelahiran hidup dari target 91,42 per 100.000 kelahiran hidup,
menurun dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 91,92 per 100.000
kelahiran hidup. Tiga penyebab tertinggi kematian ibu pada tahun 2018
adalah penyebab lain-lain yaitu 32,57% atau 170 orang, Preeklamsi/Eklamsi
yaitu sebesar 31,32% atau sebanyak 163 orang dan perdarahan yaitu 22,8%
atau sebanyak 119 orang dan penyebab paling kecil adalah infeksi sebesar
3,64% atau sebanyak 19 orang. Sedangkan Angka Kematian Bayi pada Tahun
2018 berada pada posisi 23 per 1.000 kelahiran hidup (angka estimasi dari
3
BPS Provinsi) dari target yaitu 24 per 1.000 kelahiran hidup, Angka
Kematian Bayi Jawa Timur sampai dengan tahun 2018 sudah di bawah target
Nasional. Sementara penyebab kematian bayi di antaranya berat bayi lahir
rendah (BBLR), asfiksia (gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan),
kelainan bawaan juga tetanus (Dinkes Jatim, 2019). Sehingga dapat
disimpulkan AKI dan AKB sudah memenuhi target provinsi Jawa Timur.
Kondisi Angka Kematian IBU (AKI) di Kabupaten Madiun pada tahun
2018 yaitu sebesar 65,80 per 100.000 KH (Dinkes Jatim, 2019). Penyebab
kematian ibu pada tahun 2017 adalah pre eklamsia dan eklamsia sebanyak 5
kasus, emboli air ketuban 3 kasus, jantung terdapat 2 kasus, sedangkan oedem
paru, HIV, perdarahan dan sepsis terdapat 1 kasus (Dinkes Kabupaten
Madiun, 2018). Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Madiun
tahun 2018 sebanyak 59 per 1.000 KH (Dinkes Jatim, 2019). Penyebab
kematian bayi (neonatal) disebabkan karena Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)
45,2% (19 kasus), asfiksi 33,3% (14 kasus), sepsis 3% (3 kasus) dan lain - lain
(5 kasus) (Dinkes Kabupaten Madiun, 2018). Dapat disimpulkan bahwa AKI
di Kabupaten Madiun tahun 2018 sudah memenuhi target MDGs maupun
SDGs sedangkan angka kematian bayi (AKB) tersebut belum memenuhi target
MDGs dan SDGs.
Ukuran keberhasilan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
keluarga akan dievaluasi melalui indikator yang mengacu pada Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 dan penjabaran RPJMN
pertahun (RKP) yang diturunkan dalam Renja K/L. Beberapa indikator yang
digunakan adalah dengan memberikan buku Kesehatan Reproduksi Calon
Pengantin oleh KUA, persalinan di fasilitas kesehatan, kunjungan neonatal
pertama (KN1), ibu hamil mendapat pelayanan antenatal (K4), Puskesmas
yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan
Komplikasi (P4K), Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil,
Puskesmas melaksanakan penjaringan kesehatan peserta didik kelas 1, 7 dan
10, puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan remaja, dan pemanfaatan
buku KIA. Selain itu indikator yang digunakan untuk penilaian terhadap
4
pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dilakukan dengan melihat
cakupan K1 dan K4, pelayanan kesehatan nifas yaitu dengan cakupan
kunjungan nifas (KF) dan KB yang keberhasilannya dapat dilihat dari
cakupan KB aktif (Kemenkes RI, 2018a).
Cakupan ibu hamil K1 di Indonesia tahun 2018 sebesar 95,65%,
sedangkan cakupan ibu hamil K4 pada tahun 2018 sebesar 88,03%.
Meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 87,3%. Jika
dibandingkan dengan target Rencana Strategis (Renstra) Kementerian
Kesehatan tahun 2018 yang sebesar 78% capaian tahun 2018 telah mencapai
target. Di indonesia pada tahun 2018 terdapat 90,32% persalinan yang
ditolong tenaga kesehatan. Sementara ibu hamil yang menjalani persalinan
dengan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
sebesar 86,28%. Secara nasional, indikator pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan (PF) telah memenuhi target Renstra
yang sebesar 82%. Sedangkan cakupan kunjungan nifas (KF3) di Indonesia
menunjukkan kecenderungan peningkatan dari 17,9% pada tahun 2008
menjadi 85,92% pada tahun 2018. Capaian kunjungan neonatal (KN1) di
Indonesia pada tahun 2018 sebesar 97,36% dari target Renstra sebesar 85%.
Sedangkan cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap), pada tahun
2018 sebesar 91,39% sudah menenuhi target Renstra sebesar 85%. Menurut
BKKBN, KB aktif di antara PUS tahun 2018 sebesar 63,27%, hampir sama
dengan tahun sebelumnya yang sebesar 63,22% (Kemenkes RI, 2019b).
Sehingga dapat disimpulkan bahwa masih banyak ibu hamil yang melakukan
kunjungan pertama pelayanan antenatal tetapi tidak meneruskan ke
kunjungan K4 sehingga kehamilan terlepas dari pemantauan tenaga
kesehatan.
Capaian cakupan ibu hamil K1 Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018
adalah 99,44%, sedangkan capaian cakupan K4 Provinsi Jawa Timur tahun
2018 adalah 91,15% dari target 78%. Capaian cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan (PF) pada tahun 2018
sebesar 95,56% dari target 82%. Cakupan kunjungan nifas (KF3) tahun 2018
5
sebesar 94,59%. Cakupan kunjungan neonatal (KN1) di Jawa Timur 2018
sebesar 100, 21% dari target 85%. Sedangkan cakupan KN lengkap tahun
2018 sebesar 98,32%. Cakupan KB aktif di Jawa Timur tahun 2018 sebesar
65,69% dari target 66% (Kemenkes RI, 2019b). Sehingga dapat disimpulkan
cakupan KB aktif di Jawa Timur belum memenuhi target.
Sementara itu di Kabupaten Madiun Cakupan Pelayanan KI pada tahun
2018 sebesar 98,8% dan Cakupan Pelayanan K4 sebesar 91,3% dari 10.030
ibu hamil. Untuk cakupan pertolongan persalinan yang ditolong oleh tenaga
kesehatan (Linakes) pada tahun 2018 sebesar 8,839 kelahiran atau sebesar
92,3%, Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Madiun pada tahun 2018 yaitu
92,1%. Cakupan KN 1 pada tahun 2018 adalah 97,0%, sedangkan KN
lengkap tahun 2018 sebesar 96,3%. Dari keseluruhan cakupan tersebut belum
ada yang memenuhi target dari SPM (Standar Pelayanan Minimal) yaitu
sebesar 100%. Cakupan pelayanan KB aktif tahun 2018 sebesar 79,4%, jika
dibandingkan dengan tahun 2017 menurun drastis yaitu 93,85%. (Dinkes
Jatim, 2019). Sehingga dapat disimpulkan cakupan K1, K4, Pn, KF, KN1 dan
KN Lengkap belum memenuhi target SPM dan terdapat kesenjangan antara
K1 dan K4 yang berarti bahwa masih banyak ibu hamil yang tidak
melanjutkan pemeriksaan kehamilan sampai K4 sehingga terlepas dari
pemantauan tenaga kesehatan. Serta cakupan KB aktif menurun drastis
dibandingkan tahun sebelumnya.
Penyebab AKI dan AKB di Indonesia masih tinggi dapat dilihat dari
capaian cakupan yang masih belum memenuhi target. Adanya kesenjangan
antara cakupan K1 dan K4 hal ini bisa dikarenakan bumil yang kontak pada
petugas kesehatan banyak yang tidak pada Trisemester pertama (K1 Murni)
sehingga masih perlu kunjungan rumah yang lebih intensif oleh bidan serta
kemitraan bidan dan dukun perlu untuk lebih ditingkatkan (Dinkes Jatim,
2019). Cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan masih belum
memenuhi target, hal ini dapat disebabkan karena askes ke fasilitas kesehatan
yang relatif sulit (Kemenkes RI, 2019b). Tidak terpenuhinya cakupan KN 1
dan KN Lengkap dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan terkait
6
pelayanan kesehatan bayi baru lahir atau kurangnya kepatuhan petugas dalam
menjalankan pelayanan sesuai pedoman (Kemenkes RI, 2018a). Serta
menurunnya cakupan pelayanan KB aktif di Kabupaten Madiun.
Dampak AKI yang tinggi disuatu wilayah menggambarkan derajat
kesehatan masyarakat yang rendah dan berpotensi menyebabkan kemunduran
ekonomi dan sosial dilevel rumah tangga, komunitas, dan nasional. Namun,
dampak terbesar kematian ibu yang berupa penurunan kualitas hidup bayi dan
anak menyebabkan goncangan dalam keluarga selanjutnya mempengaruhi
tumbuh kembang anak (Aeni, 2013).
Pemerintah Indonesia sudah menetapkan berbagai program sebagai
upaya untuk menurunkan AKI dan AKB. Upaya percepatan penurunan AKI
dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses
pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu
hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas
pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi,
perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan
keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan. Pelayanan kesehatan ibu
hamil harus memenuhi frekuensi minimal di tiap trimester, yaitu minimal satu
kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), minimal satu kali
pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan minimal dua kali
pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai menjelang
persalinan). Selain itu, upaya kesehatan ibu lainnya, yaitu pemberian
imunisasi Tetanus Toksoid Difteri (Td) bagi ibu hamil, pelaksanaan kelas ibu
hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi
(P4K) (Kemenkes RI, 2019b).
Upaya peningkatan kesehatan ibu bersalin yaitu dengan mendorong
agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter
spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan,
dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Persalinan yang ditolong tenaga
kesehatan terbukti berkontribusi terhadap turunnya risiko kematian ibu.
Demikian pula jika persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan,
7
juga akan semakin menekan risiko kematian ibu. Untuk daerah dengan akses
sulit, Kementerian Kesehatan mengembangkan program Kemitraan Bidan
dan Dukun serta Rumah Tunggu Kelahiran. Para dukun diupayakan bermitra
dengan bidan dengan hak dan kewajiban yang jelas. Pemeriksaan kehamilan
dan pertolongan persalinan tidak lagi dikerjakan oleh dukun, namun dirujuk
ke bidan (Kemenkes RI, 2019b).
Upaya peningkatan kesehatan ibu nifas yaitu dengan pelayanan
kesehatan ibu nifas harus dilakukan minimal tiga kali sesuai jadwal yang
dianjurkan, yaitu pada enam jam sampai dengan tiga hari pasca persalinan,
pada hari ke empat sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari
ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan.Jenis pelayanan kesehatan
ibu nifas yang diberikan meliputi pemeriksaan tanda vital (tekanan darah,
nadi, nafas, dan suhu), pemeriksaan tinggi puncak rahim (fundus uteri),
pemeriksaan lokhia dan cairan per vaginam lain, pemeriksaan payudara dan
pemberian anjuran ASI eksklusif, pemberian komunikasi, informasi, dan
edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga
berencana pasca persalinan, pelayanan keluarga berencana pasca persalinan
(Kemenkes RI, 2019b).
Upaya pelayanan kesehatan bagi neonatus minimal dilakukan 3 kali
yaitu pada umur 6-48 jam, umur 3-7 hari, dan umur 8-28 hari. Indikator yang
menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko
kematian pada periode neonatal yaitu 6-48 jam setelah lahir adalah cakupan
Kunjungan Neonatal Pertama atau KN1. Pelayanan dalam kunjungan ini
(Manajemen Terpadu Balita Muda) antara lain meliputi termasuk konseling
perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, pemberian vitamin K1 injeksi dan
Hepatitis B0 injeksi (bila belum diberikan) (Kemenkes RI, 2019b).
Penulis telah melakukan studi pendahuluan di PMB Ny. Siti Rohmani
S.ST di wilayah Kabupaten Madiun, sejak bulan Januari-Desember tahun
2019 didapatkan jumlah pasien K1 sejumlah 95 orang, K4 sejumlah 78 orang,
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sejumlah 93 orang, KF
sejumlah 93 orang, KN lengkap sejumlah 93 bayi, dan ibu yang
8
menggunakan alat kontrasepsi sejumlah 723 orang. Tidak ada kematian ibu
dan bayi (Data Primer, 2020).
Kematian ibu dan bayi setidaknya dapat diantisipasi dengan
meningkatkan pelayanan berkualitas yaitu dengan dilakukannya asuhan
kebidanan secara Continuity Of Care (COC) yaitu asuhan yang komprehensif
pada ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus, dan Keluarga Berencana. Continuity
Of Care (COC) merupakan hal yang mendasar dalam model praktek
kebidanan untuk memberikan asuhan yang holistik, membangun kemitraan
yang berkelanjutan untuk memberikan dukungan, dan membina hubungan
saling percaya antara bidan dengan klien. Continuity Of Care memastikan ibu
dan bayi mendapatkan asuhan yang terbaik dari bidan pada seluruh periode
kehamilan dan melahirkan (Astuti dkk, 2017). Dengan dilaksanakannya
asuhan kebidanan tersebut diharapkan ibu dapat menjalani kehamilan sampai
Keluarga Berencana tanpa penyulit apapun.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan
asuhan kebidanan pada masa hamil, bersalin, nifas, neonatus, sampai
Keluarga Berencana Pada Ny. “T” di PMB Ny. Siti Rohmani, S.ST.,
Kabupaten Madiun secara Continuity Of Care (COC) sebagai Laporan Tugas
Akhir.
B. Pembatasan Masalah
Ruang lingkup asuhan kebidanan yang diberikan kepada ibu hamil TM III,
bersalin, nifas, neonatus, dan Keluarga Berencana secara Continuity Of Care.
C. Tujuan
1. Tujuan Umum
Memberikan asuhan kebidanan secara continuity of care pada ibu
hamil,bersalin, nifas, neonatus dan KB dengan menggunakan pendekatan
manajemen kebidanan.
2. Tujuan Khusus
a. Memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil meliputi :
9
1) Melakukan pengkajian
2) Menyusun diagnosa kebidanan sesuai dengan prioritas
3) Merencanakan asuhan kebidanan secara kontinyu
4) Melaksanakan asuhan kebidanan secara kontinyu
5) Melakukan evaluasi asuhan kebidanan yang telah dilakukan
6) Mendokumentasikan asuhan kebidanan yang telah dilakukan
dengan SOAP notes
b. Memberikan asuhan kebidanan pada ibu bersalin meliputi :
1) Melakukan pengkajian
2) Menyusun diagnosa kebidanan sesuai dengan prioritas
3) Merencanakan asuhan kebidanan secara kontinyu
4) Melaksanakan asuhan kebidanan secara kontinyu
5) Melakukan evaluasi asuhan kebidanan yang telah dilakukan
6) Mendokumentasikan asuhan kebidanan yang telah dilakukan
dengan SOAP notes
c. Memberikan asuhan kebidanan pada ibu nifas meliputi :
1) Melakukan pengkajian
2) Menyusun diagnosa kebidanan sesuai dengan prioritas
3) Merencanakan asuhan kebidanan secara kontinyu
4) Melaksanakan asuhan kebidanan secara kontinyu
5) Melakukan evaluasi asuhan kebidanan yang telah dilakukan
6) Mendokumentasikan asuhan kebidanan yang telah dilakukan
dengan SOAP notes
d. Memberikan asuhan kebidanan pada neonatus meliputi :
1) Melakukan pengkajian
2) Menyusun diagnosa kebidanan sesuai dengan prioritas
3) Merencanakan asuhan kebidanan secara kontinyu
4) Melaksanakan asuhan kebidanan secara kontinyu
5) Melakukan evaluasi asuhan kebidanan yang telah dilakukan
6) Mendokumentasikan asuhan kebidanan yang telah dilakukan
dengan SOAP notes
10
e. Memberikan asuhan kebidanan pada KB meliputi :
1) Melakukan pengkajian
2) Menyusun diagnosa kebidanan sesuai dengan prioritas
3) Merencanakan asuhan kebidanan secara kontinyu
4) Melaksanakan asuhan kebidanan secara kontinyu
5) Melakukan evaluasi asuhan kebidanan yang telah dilakukan
6) Mendokumentasikan asuhan kebidanan yang telah dilakukan
dengan SOAP notes
D. Ruang Lingkup
1. Sasaran
Sasaran subyek asuhan kebidanan ditujukan kepada ibu dengan
menerapkan pelayanan kebidanan secara Continuity Of Care mulai hamil
TM III, bersalin, nifas, neonatus dan KB.
2. Tempat
Lokasi yang dipilih untuk memberikan asuhan kebidanan di Praktek
Mandiri Bidan (PMB) Ny. Siti Rohmani, SST., Dagangan, Kabupaten
Madiun.
3. Waktu
Waktu yang diperlukan untuk menyusun Laporan Tugas Akhir sampai
memberikan asuhan kebidanan adalah bulan April-Agustus 2020.
E. Manfaat
1. Manfaat Teoristis
Menambah pengetahuan, serta sebagai bahan penerapan ilmu kebidanan,
khususnya mengenai asuhan kebidanan secara Continuty Of Care pada ibu
hamil TM III, bersalin, nifas, neonatus, dan KB
2. Manfaat praktis
a. Bagi Pasien dan Keluarga
Untuk memberikan informasi tentang kehamilan TM III, persalinan,
nifas, neonatus, dan Keluarga Berencana (KB) dan ibu mendapatkan
11
pelayanan kebidanan secara Continuity Of Care mulai dari
kehamilan TM III, persalinan, nifas, neonatus, dan KB sehingga
dapat mengantisipasi apabila terjadi penyulit.
b. Bagi profesi bidan
Mengetahui pegembangan aplikasi asuhan kebidanan Continuity Of
Care mulai kehamilan TM III, persalinan, nifas, neonatus, dan
Keluarga Berencana secara nyata di lapangan dan sesuai teori yang
ada, serta dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi untuk
lahan praktek.
c. Bagi STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun
Sebagai bahan acuan bagi penulis selanjutnya, dan dapat digunakan
sebagai bahan bacaan di perpustakaan tentang asuhan kebidanan
secara Continuity Of Care pada ibu hamil TM III, bersalin, nifas,
neonatus, dan KB.
d. Bagi Penulis
Menerapkan teori dan memberikan pengalaman dalam melaksanakan
asuhan kebidanan pada ibu hamil TM III, bersalin, nifas, neonatus,
dan KB secara nyata pada klien tentang asuhan kebidanan secara
Continuity Of Care pada ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus, dan
KB.
12
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kehamilan
1. Konsep Dasar Kehamilan
a. Pengertian
Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari
spermatozoa dan ovum dan di lanjutkan dengan nidasi atu
implantasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi huingga lahirnya bayi,
kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10
bulan atau 9 bulan menurut kalender internasional. Kehamilan
terbagi menjadi 3 trimester, dimana trimester satu berlangsung dalam
12 minggu, trimester kedua 15 minggu (minggu ke-13 hingga ke-
27), dan trimester ketiga 13 minggu, minggu ke-28 hingga ke-40
(Walyani, 2015a).
Kehamilan merupakan proses alamiah, bila tidak dikelola
dengan baik akan memberikan komplikasi pada ibu dan janin dalam
keadaan sehat dan aman (Walyani, 2015a).
Kehamilan terjadi harus ada spermatozoa, ovum, pembuahan
ovum (konsepsi) dan nidasi (implantasi) hasil konsepsi
(Prawirohardjo, 2014).
b. Fisiologis Kehamilan
1) Ovulasi (pengeluaran sel telur)
Ovulasi biasanya terjadi kira-kira 14 hari sebelum
menstruasi yang akan datang, dengan kata lain, diantara dua
haid yang berurutan, indung telur akan mengeluarkan ovum,
setiap kali satu dari pvarium kanan dan lain kali dari ovarium
kiri (Walyani, 2015a).
13
2) Spermatozoa
Sperma merupakan sel gamte pria. Sel gamet ini diproduksi
di dalam testis yang terdapat di dalam skrotum (Astuti dkk,
2017).
Setiap spermatozoa terdiri atas tiga bagian yaitu kaput atau
kepala yang berbentuk lonjong agak gepeng dan mengandung
bahan nukleus, ekor dan bagian yang silindrik (leher)
menghubungkan kepala dengan ekor (Prawirohardjo, 2014).
3) Fertilisasi
Fertilisasi (pembuahan) adalah penyatuan ovum (oosit
sekunder) dan spermatozoa yang biasanya berlangsung di
ampula tuba. Untuk mencapai ovum, spermatozoa harus
melewati korona radiate (lapisan sel di luar ovum) dan zona
pelusida. Spermatozoa yang masuk ke vitelus akan kehilangan
membran nukleusnya sehingga yang tinggal hanya
pronukleusnya, sedangkan ekor spermatozoa dan
mitokondrianya berdegenerasi. Masuknya spermatozoa kedalam
vitelus membangkitkan nukleus ovum yang masih dalam
metafase untuk proses pembelahan selanjutnya (pembelahan
meiosis kedua). Sesudah anafase kemudian timbul telofase,
benda kutub (polar body) kedua menuju ruang perivitelina.
Ovum sekarang hanya mempunyai pronukleus yang haploid.
Pronukleus spermatozoa juga mengandung jumlah kromosom
yang haploid. Dalam beberapa jam setelah pembuahan terjadi,
mulailah pembelahan zigot dan dalam 3 hari terbentuk suatu
kelompok sel yang sama besarnya. Hasil konsepsi berada dalam
stadium morula. Hasil konsepsi kemudian disalurkan terus ke
pars ismika dan pars interstisialis tuba. Pertemuan inti ovum
dengan inti spermatozoa disebut konsepsi atau fertilisasi dan
membentuk zigot (Prawirohardjo, 2014).
14
4) Nidasi
Nidasi adalah masuknya atau tertanamnya hasil konsepsi ke
dalam endometrium (Walyani, 2015a)
Pada hari keempat hasil konsepsi mencapai stadium blastula
disebut blastokista atau blastocyst, suatu bentuk yang dibagian
luarnya adalah tropoblas dan dibagian dalamnya disebut massa
inner cell. Massa inner cell ini berkembang menjadi janin dan
trofoblas akan berkembang menjadi plasenta (Prawirohardjo,
2014).
5) Plasentasi
Plasentasi adalah proses pembentukan struktur dan jenis
plasenta. Setelah nidasi embrio ke dalam endometrium,
plasentasi dimulai. Pada manusia plasentasi berlangsung sampai
12-18 minggu setelah fertilisasi (Prawirohardjo, 2014).
Dalam 2 minggu pertama perkembangan hasil konsepsi,
trofoblas invasif telah melakukan penetrasi ke pembuluh darah
endometrium. Terbentuklah sinus intertrofoblas yaitu ruangan-
ruangan yang berisi darah maternal dari pembuluh-pembuluh
darah yang dihancurkan Pertumbuhan ini berjalan terus,
sehingga timbul ruangan interviler di mana vili korialis seolah-
olah terapung-apung di antara ruangan tersebut sampai
terbentuknya plasenta (Prawirohardjo, 2014).
Tiga minggu pascafertilisasi sirkulasi darah janin dini dapat
diidentifikasi dan dimulai pembentukan vili korialis. Sirkulasi
darah janin ini berakhir di lengkung kapilar di dalam vili korialis
yang ruang intervilinya dipenuhi dengan darah maternal yang
dipasok oleh arteri spiralis dan dikeluarkan melalui vena uterina.
Vili korialis seolah-olah terapung-apung di antara ruangan-
ruangan tersebut ampai terbentuknya plasenta (Prawirohardjo,
2014).
15
Lapisan desidua yang meliputi hasil konsepsi ke arah
kavum uteri disebut desidua kapsularis, yang terletak antara
hasil konsepsi dan dinding uterus disebut desidua basalis, di situ
plasenta akan dibentuk. Desidua yang meliputi dinding uterus
yang lain adalah desidua parietalis. Hasil konsepsi sendiri
diselubungi oleh jonjot-jonjot yang dinamakan vili karialis da
berpangkal pada karion. Sel-sel fibrolas mesodermal tumbuh di
sekitar embrio dan melapisi pula sebelah dalam trofoblas
(Prawirohardjo, 2014).
Dengan demikian, terbentuklah chorionic membrane yang
kelak menjadi korion. Selain itu, vili korialis yang berhubungan
dengan desidua basalis tumbuh dan bercabang-cabang dengan
baik, disisi korion disebut korion frondosum. Yang berhubungan
dengan desidua kapsularis kurang mendapat makanan, karena
hasil konsepsi bertumbuh ke arah kavum uteri sehingga lambat
laun menghilang. (Prawirohardjo, 2014).
6) Perkembangan janin
Sejak konsepsi perkembangan konseptus terjadi sangat
cepat yaitu zigot mengalami pembelahan menjadi morula (terdiri
atas 16 sel blastomer), kemudian menjadi blastokis (terdapat
cairan di tengah) yang mencapai uterus, dan kemudian sel-sel
mengelompok, berkembang menjadi embrio (sampai minggu ke-
7). Konseptus ialah semua jaringan yang membagi diri menjadi
berbagai jaringan embrio, korion, amnion dan plasenta
(Prawirohardjo, 2014).
Dalam beberapa jam setelah ovulasi akan terjadi fertilisasi
di ampula tuba. Oleh karena itu, sperma harus sudah ada di sana
sebelumnya. Berkat kekuasaan Allah SWT, terjadilah fertilisasi
ovum oleh sperma. Namun, konseptus terjadi mungkin sempura,
mungkin tidak sempurna. Kebesaran dan penciptanNya-lah yang
16
memungkinkan diferensiasi jaringan yang mengagumkan di
masa terbentuknya organ (Prawirohardjo, 2014).
Embrio akan berkembang sejak usia 3 minggu hasil
konsepsi, secara klinik pada usia gestasi 4 minggu dengan USG
akan tampak sebagai kantong gestasi berdiameter 1 cm, tetapi
embrio belum tampak. Pada minggu ke-6 dari haid terakhir -
usia konsepsi 4 minggu – embrio berukuran 5 mm, kantong
gestasi berukuran 2-3 cm. Pada saat itu akan tampak denyut
jantung secara USG. Pada akhir minggu ke-8 usia gestasi – 6
minggu usia embrio – embrio berukuran 22-24 mm, di mana
akan tampak kepala yang relative besar dan tonjolan jari.
(Prawirohardjo, 2014).
17
Tabel 2.1 Perkembangan fungsi organ janin Usia gestasi (Minggu) Organ
6 Pembentukan hidung, dagu, palatum dan tonjolan
paru. Jari-jari telah berbentuk, namun masih
tergenggam. Jantung telah terbentuk penuh.
7 Mata tampak pada muka. Pembentukan alis dan
lidah.
8 Mirip bentuk manusia, mulai pembentukan genetalia
eksterna. Sirkulasi melalui tali pusat dimulai. Tulang
mulai terbentuk.
9 Kepala meliputi separuh besar janin, terbentuk muka
janin, kelopak mata terbentuk namun tak akan
membuka sampai 28 minggu.
13-16 Janin berukuran 15 cm. Ini merupakan awal dari
trimester ke-2. Kulit janin masih transparan, telah
mulai tumbuh lanugo (rambut janin). Janin bergerak
aktif, yaitu menghisap dan menelan air ketuban.
Telah terbentuk mekonium (feces) dalam usus.
Jantung berdenyut 120-150x/menit
17-24 Komponen mata terbentuk penuh, juga sidik jari.
Seluruh tubuh diliputi oleh verniks keseosa (lemak).
Janin mempunyai reflex
25-28 Saat itu disebut permulaan trimester ke-3, di mana
terdapat perkembangan otak yang cepat. Sistem saraf
mengendalikan gerakan dan fungsi tubuh, mata sudah
membuka. Kelangsungan hidup pada periode ini
sangat sulit bila lahir. Kelangsungan hidup pada
periode ini sangat sulit bila lahir.
29-32 Bila bayi dilahirkan, ada kemungkinan untuk hidup
(50-70%). Tulang telah tebentuk sempurna, gerakan
nafas telah reguler, suhu relatif stabil.
33-36 Berat janin 1500-2500 gram. Bulu kulit janin
(lanugo) mulai berkurang, pada saat 35 minggu paru
telah matur. Janin akan dapat hidup tanpa kesulitan.
38-40 Sejak 38 minggu kehamilan disebut aterm, di mana
bayi akan memiliki seluruh uterus. Air ketuban mulai
berkurang, tetapi masih dalam batas normal.
Sumber : Prawirohardjo, 2014, Ilmu Kebidanan, Bagian Fisiologi Janin, Jakarta, halaman:
157-158.
c. Tanda-Tanda Kehamilan
1) Tanda Dugaan Hamil
a) Amenorea (berhentinya menstruasi)
Konsepsi dan nidasi menyebabkan tidak terjadi
pembentukan folikel de graaf dan ovulasi sehingga
menstruasi tidak terjadi. Lamanya amenorea dapat
diinformasikan dengan memastikan hari pertama haid
terakhir (HPHT), dan digunakan untuk memperkirakan usia
18
kehamilan dan tafsiran persalinan. Tetapi amenorea juga
dapat disebabkan oleh penyakit kronik tertentu, tumor
pituitari, perubahan dan faktor lingkungan, malnutrisi, dan
biasanya gangguan emosional seperti ketakutan akan
kehamilan (Walyani, 2015a).
b) Mual (nausea) dan muntah (emesis)
Pengaruh ekstrogen dan progesterone terjadi
pengeluaran asam lambung yang berlebihan dan
menimbulkan mual muntah yang terjadi terutama pada pagi
hari yang disebut morning sicknes. Dalam batas tertentu hal
ini masih fisiologis, tetapi bila terlampau sering dapat
menyebabkan gangguan kesehatan yang disebut dengan
hipermesis gravidarum (Walyani, 2015a).
c) Ngidam (mengingingkan makan tertentu)
Wanita hamil yang sering mengingingkan makanan
tertentu, keinginan yang demikian disebut ngidam. Ngidam
sering terjadi pada bulan bulan pertama kehamilan dan akan
menghilang dengan tuanya kehamilan (Walyani, 2015a).
d) Syncope (pingsan)
Terjadinya gangguan sirkulasi kedaerah kepala (sentral)
menyebabkan inskemia susunan saraf pusat dan
menimbulkan syncope atau pingsan. Hal ini terjadi terutama
jika berada pada tempat yang ramai, biasanya akan hilang
setelah 16 minggu (Walyani, 2015a).
e) Kelelahan
Sering terjadi pada trimester pertama, akibat ini
penurunan kecepatan basal metabolism (basal metabolism
rate-BMR) pada kehamilan yang akan meningkat sering
pertmbahan usia kehamilan alibat aktivitas metabolisme
hasil konsepsi (Walyani, 2015a).
19
f) Payudara tegang
Estrogen meningkatkan perkembangan sistem ductus
pada payudara, sedangkan progesterone menstimulasi
perkembangan sistem pada payudara. Bersama
somatomamotropin, hormone ini menimbulkan pembesaran
payudara, menimbulkan perasaan tegang dan nyeri selama
dua bulan pertama kehamilan, pelebaran putting susu serta
pengeluaran kolostrum (Walyani, 2015a).
g) Sering miksi
Desakan Rahim kedepan menyebabkan kandung kemih
cepat terasa penuh dan sering miksi. Frekuensi miksi yang
sering terjadi pada triwulan pertama akiabat desakan uterus
kandung kemih. Pada triwulan kedua umumnya keluhan ini
akan berkurang karena uterus yang membesar keluar dari
rongga panggul. Pada akhir triwulan gejala bisa timbul
karena janin mulai masuk keroongga panggul dan menekan
kembali kandung kemih (Walyani, 2015a).
h) Kontisipasi atau obstipasi
Pengaruh progesterone dapat menghambat peristaltic
usus (tonus otot menurun) sehingga kesulitan untuk BAB
(Walyani, 2015a).
i) Pigmentasi kulit
Pigmentasi terjadi pada usia kehamilan lebih 12
minggu. Terjadi akibat pengaruh hormone kortikosteroid
plasenta yang merangsng melanofor dan kulit (Walyani,
2015a).
j) Epulis
Hipertfrofi gusi disebut epulis daat terjadi bila hamil
sehingga dapat menyebabkan gusi berdarah (Marmi, 2014).
Hipertrofi papila ginggivae/gusi, sering terjadi pada
triwulan pertama (Walyani, 2015a).
20
k) Varises
Pengaruh estrogen dan progesterone menyebabkan
pelebaran pembuluh darah terutama bagi wanita yang
mempunyai bakat. Varises dapat terjadi disekitar genitalia
eksterna, kaki dan betis serta payudara. Penampakam
pembuluh darah ini dapat hilang setelah persalinan
(Walyani, 2015a).
2) Tanda kemungkinan (Probability sign)
Menurut Walyani (2015a), Tanda kemungkinan adalah
perubahan-perubahan fisiologi yang dapat diketahui oleh
pemeriksa dengan melakukan pemeriksaan fisik kepada wanita
hamil yaitu meliputi:
a) Pembesaran perut
Terjadi akibat pembesaran uterus, hal ini terjadi pada
bulan keempat kehamilan.
b) Tanda hegar
Adalah pelunakan dan dapat ditekannya isthimus uteri.
c) Tanda goodel
Adalah pelunakan serviks. Pada wanita yang tidak
hamil serviks seperti ujung hidung, sedangkan pada wanita
hamil melunak seperti bibir.
d) Tanda chadwick
Perubahan warna menjadi keunguan pada vulva dan
mukosa vagina termasuk juga porsio dan serviks.
e) Tanda piscaseck
Merupakan pembesaran uterus yang tidak simetris.
Terjadi karena ovum berimplantasi pada daerah dekat kornu
sehingga daerah tersebut berkembang lebih dulu.
f) Kontraksi Braxton hicks
Merupakan peregangan sel-sel otot uterus, akibat
meningkatnya actomsyn didalam otot uterus. Kontraksi ini
21
tidak bermitrik, sporadic, tidak nyeri, biasanya timbul pada
kehamilan delapan minggu, tetapi baru dapat diamati daeri
pemeriksaan abdominal pada trimester ketiga. Kontraksi ini
akan terus meningkat frekuensinya, lamanya dan
kekuatannya sampai mendekati persalinan.
g) Teraba ballottement
Ketukan yang mendadak pada uterus menyebabkan
janin bergerak dalam cairan ketuban yang dapat dirasakan
oleh tangan pemeriksa. Hal ini harus ada pada pemeriksaan
kehamilan karena perabaan bagian seperti bentuk janin saja
tidak cukup karena dapat saja merupakan myoma uteri.
h) Pemeriksaan tes biologis kehamilan (planotest) positif
Pemeriksaan ini untuk mendeteksi adanya human
cjorionicgonaadotropin (hCG) yang diproduksi oleh
sinsiotropoblastik sel selama kehamilan. Hormone direksi
ini peredaran darah ibu (pada plasenta darah), dan dieksresi
pada urin ibu. Hormone ini dapat mulai dideteksi pada 26
hari setelah konsepsi dan meningkat dengan cepat pada hari
ke 30-60. Tingkat tertinggi pada hari 60-70 usia gestasi,
kemudian menurun pada hari ke 100-300.
3) Tanda pasti (Positive Sign)
Tanda pasti adalah tanda yang menunjukkan langsung
keberadaan janin yang dapat dilihat langsung oleh pemeriksa
(Walyani, 2015a).
a) Gerakan janin dalam Rahim
Gerakan ini harus dapat diraba dengan jelas oleh
pemeriksa. Gerakan janin baru dapat dirasakan pada usia
kehamilan 20 minggu (Walyani, 2015a).
b) Denyut jantung janin
Dapat didengar pada usia 12 minggu dengan
menggunakan alat fetal electrocardiograf (misalnya dopler).
22
Dengan stethoscope laenec, DJJ baru dapat didengar pada
usia kehamilan 18-20 minggu (Walyani, 2015a).
c) Bagian-bagian janin
Bagian-bagian janin yaitu bagian besar janin (kepala
dan bokong) serta bagian kecil janin (lengan dan kaki) dapat
diraba dengan jelas pada usia kehamilan lebih sempurna
lagi menggunakan USG (Walyani, 2015a).
d) Kerangka janin
Kerangka janin dapat dilihat dengan foto rontgen
maupun USG (Walyani, 2015a).
4) Diagnosis kehamilan
Menurut Walyani (2015a), diagnosis dibuat untuk
menentukan hal-hal sebagai berikut:
Tabel 2.2 Diagnosis Kehamilan No. Kategori Gambaran
1. Kehamilan normal 1. Ibu sehat
2. Tidak ada riwayat obstetri buruk
3. Ukuran uterus sama/sesuai usia kehamilan
4. Pemeriksaan fisik dan laboratorium normal
2 Kehamilan dengan
masalah khusus
Seperti masalah keluarga atau psikososial,
kekerasan dalam rumah tangga, kebutuhan
finansial, dan lain-lain
3 Kehamilan dengan
masalah kesehatan
yang membutuhkan
rujukan segera
Seperti hipertensi, anemia berat, preeklamsi,
pertumbuhan janin terhambat, infeksi saluran
kemih, penyakit kelamin dan kondisi lain-lain yang
dapat memburuk selama kehamilan
4 Kehamilan dengan
kondisi
kegawatdaruratan yang
membutuhkan rujukan
segera
Seperti perdarahan, eklamsi, ketuban pecah dini,
atau kondisi-kondisi kegawatdaruratan lain pada
ibu dan bayi
Sumber: Walyani, 2015a, Asuhan Kebidanan pada Kehamilan, Bagian Konsep Dasar
Kehamilan , Yogyakarta, halaman, 74.
d. Perubahan Fisiologi Pada Kehamilan
1) Uterus
Selama kehamilan uterus akan beradaptasi umtuk menerima
dan melindungi hasil konsepsi (janin, plasenta, amnion) sampai
persalinan. Uterus mempunyai kemampuan yang luar biasa
untuk bertambah besar dengan cepat selama kehamilan dan
23
pulih kembali seperti keadaan semula dlam beberapa minggu
setelah persalinan. Pada perempuan tidak hamil uterus
mempunyai berat 70 g dan kapasitas 10 ml atau kurang. Selama
kehamilan, uterus akan berubah menjadi suatu organ yang
mampu menampung janin plasenta, dan cairan amnion rata-rata
pada akhir kehamilan volume totalnya mencapai 5 l bahkan
dapat mencapai 20 l atau lebih dengan berat rata-rata 1100 g
(Prawirohardjo, 2014).
2) Ovarium
Proses ovulasi selama kehamilan akan terhenti dan
pematangan folikel baru juga ditunda. Hanya satu korpus luteum
yang dapat ditemukan di ovarium, folikel ini akan berfungsi
maksimal selama 6-7 minggu awal kehamilan dan setelah itu
akan berperan sebagai penghasil progesteron dalam jumlah yang
relatif yang relatif minimal (Prawirohardjo, 2014).
3) Vagina dan perineum
Selama kehamilan peningkatan vaskularisasi dan hiperemia
terlihat jelas pada kulit dan otot-otot di perineum dan vulva,
sehingga pada vagina akan terlihat berwarna keunguan yang
dikenal dengan tanda Chadwick. Perubahan ini meliputi
penipisan mukosa dan hilangnya sejumlah jaringan ikat dan
hipertrofi dari sel –sel otot polos. Dinding vagina mengalami
banyak perubahan yang merupakan persiapan untuk mengalami
peregangan pada waktu persalinan dengan meningkatnya
ketebalan mukosa, mengendornya jaringan ikat, dan hipertrofi
sel otot polos. Perubahan ini mengakibatkan bertambah
panjangnnya dinding vagina (Prawirohardjo, 2014).
4) Kulit
Pada kulit dinding perut terjadi perubahan warna menjadi
kemerahan, kusam, dan kadang-kadang juga akan mengenai
daerah payudara dan paha. Perubahan ini dikenal dengan nama
24
striae gravidarum. Pada banyak perempuan kulit di garis
pertengahan perutnya (linea alba) akan beubah menjadi hitam
kecoklatan yang disebut dengan line nigra. Kadang-kadang akan
muncul dalam ukuran yang bervariasi pada wajah dan leher
yang disebut dengan chloasma atau melisma gravidarum. Selain
itu, pada areola dan daerah genital juga akan terlihat pigmentasi
yang berlebihan. Pigmentasi yang berlebihan itu biasanya akan
hilang atau sangat jauh berkurang setelah persalinan
(Prawirohardjo, 2014).
Perubahan ini dihasilkan dari cadangan melanin pada
daerah epidermal dan dermal yang penyebab pastinya belum
diketahui. Adanya peningkatan kadar serum melanocyte
stimulating hormone pada akhir bulan kedua masih sangat
dragukan sebagai penyebabnya. Estrogen dan progesterone
diketahui mempunyai peran dalam melangenesis dan diduga
bias menjadi faktor pendorongnya (Prawirohardjo, 2014).
5) Payudara
Pada awal kehamilan perempuan akan merasakan
payudarannya lebih lunak, setelah bulan kedua payudara akan
bertambah ukurannya dan vena-vena di bawah kulit akan lebih
terlihat.puting payudara akan lebih besar, kehitaman, dan tegak.
Setelah bulan pertama suatu cairan berwarna kuning yang di
sebut kolostrum dapat keluar (Prawirohardjo, 2014).
6) Perubahan metabolik
Sebagian besar penambahan berat badan selama kehamilan
berasal dari uterus dan isinya. Diperkirakan selama kehamilan
berat badan akan bertambah 12,5 kg. Pada TM 2 dan 3
dianjurkan untuk menambah berat badan per minggu 0,4 kg.
Hasil konsepsi, uterus, dan darah ibu secara relatif mempunyai
kadar protein yang lebih tinggi dibandingkan lemak dan
karbohidrat (Prawirohardjo, 2014).
25
Terjadi perubahan metabolisme. Metabolisme basal
meningkat. Masuknya makanan sangat berpengaruh untuk
metabolisme ibu dan janin. Ketidak seimbangan akan
menyebabkan berbagai masalah seperti hipertensi, diabetes dan
lain-lain (Marmi, 2014).
7) Sirkulasi darah
Volume darah akan meningkat secara progresif mulai
minggu 6-8 kehamilan dan mencapai puncaknya pada minggu
ke 32-34 dengan perubahan kecil setelah minggu tersebut
(Prawirohardjo, 2014).
Eritropoetin ginjal akan meningkatkan jumlah sel darah
merah sebanyak 20-30%, tetapi tidak sebanding dengan
peningkatan volume plasma sehingga akan mengakibatkan
hemodilusi dan penurunan konsentrasi hemoglobin dari 15 g/dl
menjadi 12,5 g/dl, dan pada 6% perempuan bisa mencapai di
bawah 11 g/dl (Prawirohardjo, 2014).
8) Sistem respirasi
Selama kehamilan sirkum ferensia torak akan bertambah 6
cm, tetapi tidak mencukupi penurunan kapasitas residu
fungsional dan volume residu paru-paru karena pengaruh
diafragma yang naik 4cm selama kehamilan. Frekuensi
pernafasan hanya mengalami sedikit perubahan selama
kehamilan, tetapi volume tidak, volume ventilasi per menit dan
pengambilan oksigen per menit akan bertambah secara
signifikan pada kehamilan lanjut. Akan mencapai puncaknya
pada minggu ke 37 (Prawirohardjo, 2014).
9) Traktus disgestivus
Seiring dengan makin besarnya uterus, lambung dan usus
akan bergeser, perubahan yang nyata akan terjadi pada
penurunan motilitas otot polos pada traktus digestivus dan
penurunan sekresi asam hidroklorid dan peptin di lambung
26
sehingga akan menimbulkan gejala berupa pyrosis (heartburn)
yang disebabkan oleh refluks asam lambung ke asofagus bawah
sebagai akibat perubahan posisi lambung dan menurunnya tonus
sfingter esofagus bagian bawah. Mual terjadi akibat penurunan
asam hidroklorid dan penurunan motilitas, serta konstipasi
sebagai akibat penurunan motilitas usus besar (Prawirohardjo,
2014).
Gusi akan menjadi lebih hiperemis dan lunak sehingga
trauma sedang saja bisa menyebabkan perdarahan. Epulsi
selama kehamilan akan muncul, tetapi setelah persalinan akan
berkurang secara spontan. Konstipasi dan peningkatan tekanan
vena pada bagian bawah karena pembesaran uterus
(Prawirohardjo, 2014).
10) Traktus urinarius
Pada bulan pertama kehamilan kandung kemih akan
tertekan oleh uterus yang mulai membesar sehingga
menimbulkan sering berkemih. Keadaan ini akan hilang dengan
makin tuanya kehamilan bila uterus keluar dari rongga panggul.
Pada akhir kehamilan, jika kepala janin sudah mulai turun ke
pintu atas panggul, keluhan itu akan timbul kembali
(Prawirohardjo, 2014).
11) Sistem Endokrin
Selama kehamilan normal kelenjar hipofisis akan membesar
± 135 %. Akan tetapi kelenjar ini tidak begitu mempunyai arti
penting dalam kehamilan. Pada perempuan yang mengalami
hipofisektomi persalinan dapat berjalan dengan lancar. Hormon
prolaktin akan meningkat 10x lipat pada saat kehamilan aterm.
Sebaliknya, setelah persalinan konsentrasinya pada plasma akan
menurun (Prawirohardjo, 2014).
27
12) Sistem muskulosketal
Lordosis yang progresif akan menjadi bentuk yang umum
pada kehamilan. Akibat kompensasi dari pembesaran uterus ke
posisi anterior, lordosis menggeser pusat daya berat ke belakang
ke arah dua tungkai. Sendi sakroilliaka, sakrokoksegis dan pubis
akan meningkatkan mobilitasnya, yang diperkirakan karena
pengaruh hormonal. Mobilitas tersebut dapat mengakibatkan
perubahan sikap ibu dan pada akhirnya menyebabkan perasaan
tidak enak pada bagian bawah punggung terutama pada akhir
kehamilan (Prawirohardjo, 2014).
e. Perubahan Psikologis Pada Kehamilan
Menurut Astuti dkk (2017), perubahan psikologi pada ibu hamil
yaitu :
1) Perubahan pada Trimester 1
Pada kehamilan trimester 1, adaptasi psikologis yang harus
dilakukan oleh ibu yaitu menerima kenyataan bahwa dirinya
sedang hamil. Seorang ibu yang menginginkan kehamilannya
akan segera mencari kebenaran secara medis bahwa memang
benar dirinya hamil. Tingkat penerimaan diri ibu hamil akan
tercermin dalam respons emosionalnya, dan kesiapan atau
penyambutan kehamilannya.
a) Respons Emosional
Berbagai respons emosional pada trimester 1 yang
dapat muncul berupa perasaan ambivalen, kekecewaan,
penolakan, kecemasan, depresi, dan kesedihan. Selain itu
perubahan mood akan lebih cepat terjadi bahkan ibu
biasanya menjadi lebih sensitif. Rasa sedih hingga berurai
air mata, rasa marah, dan rasa sukacita datang silih berganti
tanpa penyebab yang jelas. Perubahan mood ini terkait
dengan perubahan hormonal, namun masalah seksual dan
28
perasaan takut nyeri persalinan diduga memicu perubahan
ini.
Pada trimester pertama ini, akan muncul sejumlah
ketidaknyamanan, misalnya mual, kelelahan, perubahan
nafsu makan, emosional, dan cepat marah. Kemungkinan
hal ini mencerminkan konflik atau depresi yang dialami
selain pengingat akan kehamilannya. Pada kehamilan
trimester pertama, ekspresi seksual bersifat individual.
Selain faktor fisik, emosi, serta interaksi dan masalah
disfungsi seksual dapat berperan terhadap perbedaan
perasaan yang muncul. Umumnya, rasa keinginan seksual
ibu akan menurun jika ibu merasa mual, letih, depresi, nyeri
payudara, khawatir, dan cemas.
Faktor yang mempengaruhi respons emosional terhadap
kehamilan meliputi :
(1) Faktor pribadi/individu :
(a) Faktor biologi dan genetic
(b) Kepribadian
(c) Kepercayaan diri
(d) Riwayat masa lalu
(2) Faktor Keluarga
(a) Hubungan dengan ayah dan anak
(b) Harapan orang lain terhadap ibu dan bayi
(3) Faktor Rumah Tangga
(a) PendapatanSumber daya untuk membesarkan anak
(b) Ketersediaan perawatan anak
(4) Masyarakat
(a) Keamanan
(b) Ketersediaan layanan
(c) Stigma
29
b) Penyambutan Sukacita
Reaksi menyambut kehamilan, teurtama pada seorang
ibu yang sedang merencanakan kehamilannya, biasanya
diawali dengan rasa tidak percaya bahwa dirinya hamil. Ia
akan mencari bukti bahwa dirinya memang benar hamil dari
setiap tanda yang berubah dari tubuhnya. Peningkatan berat
badan pada trimester pertama dianggap sebagai bukti bahwa
ia hamil. Ia akan berpikir bahwa janin sedang tumbuh di
dalam perutnya, walaupun janin tersebut tidak tampak nyata
secara fisik. Reaksi ini akan berbanding terbalik pada
wanita dengan kehamilan yang tidak diinginkan (misalnya
remaja yang hamil diluar nikah). Ia akan mengurangi makan
atau justru menahan laparnya karena khawatir
kehamilannya diketahui oleh orang lain atau agar tidak
terlihat hamil oleh orang lain.
2) Perubahan pada Trimester 2
Secara umum, pada trimester kedua ini ibu akan merasa
lebih baik dan sehat karena terbebas dari ketidaknyamanan
kehamilan, misalnya mual dan letih. Perubahan psikologis pada
trimester kedua ini dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu
sebelum adanya pergerakan janin yang dirasakan ibu
(prequickening) dan setelah adanya pergerakan janin yang
dirasakan oleh ibu (postquickening).
a) Sebelum Gerakan Janin Dirasakan
Pada tahap ini, akan terjadi proses perubahan identitas
pada ibu hamil yaitu dari penerima kasih sayang menjadi
pemberi kasih sayang karena ia harus menyiapkan dirinya
berperan menjadi seorang ibu. Selama proses berlangsung,
umumnya ia akan mengevaluasi kembali hubungan
interpersonal dengan ibunya yang telah terjadi selama ini,
sehingga saat kondisi seperti itu wanita tersebut akan
30
belajar bagaimana ia akan mengembangkan perannya
menjadi seorang ibu yang harus menyayangi, serta
bagaimana hubungannya dengan anak yang akan
dilahirkannya.
b) Setelah Gerakan Janin Dirasakan
Umumnya, pada bulan kelima ibu hamil akan mulai
meraskan gerakan janin. Gerakan ini akan menimbulkan
kesadaran bahwa terdapat anak yang semakin nyata di
dalam kandungannya sebagai individu yang terpisah. Ibu
hamilakan merasakan bahwa anak yang sedang dalam
kandungannya perlu dirawat. Ibu akan lebih memusatkan
perhatiannya pada kehamilannya, apalagi jika ia pernah
mendengarkan denyut jantung janin yang pernah
didengarnya saat melakukan kunjungan antenatal.
3) Perubahan pada Trimester 3
Pada kehamilan trimester ketiga, ibu akan lebih nyata
mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran anaknya.
a) Kekhawatiran/kecemasan dan waspada
Setiap kali janin bergerak dan perut yang semakin
membesar akan mengingatkan ibu hamil pada bayinya.
Rasa cemas dapat timbul jika ibu memikirkan dan khawatir
bayinya akan lahir sebelum waktunya, sehingga akan lebih
memperhatikan serta waspada terhadap munculnya tanda
persalinan. Kecemasan juga dapat timbul akibat
kekhawatiran akan proses persalinannya, takut terhadap rasa
sakit, dan takut terjadi komplikasi persalinan pada dirinya
maupun bayinya. Pada trimester ketiga ini, libido cenderung
menurun kembali yang disebabkan munculnya kembali
ketidaknyaman fisiologis, serta bentuk dan ukuran tubuh
yang semakin membesar. Khawatir akan kehilangan
perhatian khusus yang ia terima dari orang sekitarnya saat ia
31
hamil dapat membuat ibu merasa sedih selain merasa akan
berpisah dari bayinya. Dukungan serta perhatian dari suami
dan keluarga sangat berguna pada saat ini.
b) Persiapan Menunggu Kelahiran
Menjelang akhir trimester ketiga, umumnya ibu hamil
tidak sabar untuk menjalani persalinan dengan perasaan
yang bercampur antara sukacita dan rasa takut. Kesiapan
untuk menghadapi persalinan biasanya muncul sebagai
akibat dari keinginannya yang kuat untuk melihat hasil
akhir dari kehamilannya.
Peran bidan sangat dibutuhkan oleh ibu hamil maupun
suaminya untuk dapat melakukan adaptasi psikologis
selama kehamilannya dengan baik. Bidan diharapkan dapat
memberi dukungan emosional, memberikan informasi dan
saran, mengurangi kecemasan, mengurangi stres, serta
mendeteksi gangguan psikologis dan/atau mengidentifikasi
faktor yang dapat menimbulkan gangguan tersebut.
f. Kebutuhan Dasar Ibu Hamil
1) Kebutuhan Fisik
Meliputi Oksigen, nutrisi, personal hygiene, pakaian, seksual,
mobilisasi dan body mekanik, exercise/senam hamil,
istirahat/tidur, imunisasi, travelling, persiapan laktasi, persiapan
kelahiran bayi, memantau kesejahteraan bayi, ketidaknyamanan
dan cara mengatasinya, kunjungan ulang, pekerjaan dan tanda
bahaya kehamilan.
a) Oksigen
Kebutuhan oksigen adalah kebutuhan yang utama pada
manusia termasuk ibu hamil. Berbagai gangguan
pernapasan bisa terjadi saat hamil sehingga mengganggu
pemenuhan kebutuhan oksigen pada ibu yang akan
berpengaruh pada bayi di kandungan (Walyani, 2015a).
32
Untuk mencegah hal tersebut dan untuk memenuhi
kebutuhan oksigen maka ibu hamil pelu melakukan:
(1) Latihan nafas melalui senam hamil
(2) Tidur dengan bantal lebih tinggi
(3) Makan tidak terlalu banyak
(4) Kurangi atau hentikan rokok
(5) Konsul ke dokter bila ada kelainan atau gangguan
pernapasan seperti asma dan lain-lain (Walyani,
2015a).
b) Nutrisi
Gizi pada waktu hamil harus ditingkatkan hingga 300
kalori per hari, ibu hamil harusnya mengonsumsi yang
mengandung protein, zat besi, dan minum cukup cairan
(menu seimbang) (Walyani, 2015a).
(1) Kebutuhan Nutrisi Ibu Hamil TM I
(a) Minggu ke 1-24
Ibu harus mengonsumsi berbagai jenis
makanan berkalori tinggi untuk mencukupi
kebutuhan kalori yang bertambah 170 kalori (setara
1 porsi nasi putih). Tujuannya agar tubuh
menghasilkan cukup energy, yang diperlukan janin
yang tengah terbentuk pesat. Konsumsi minimal
2000 kilo kalori per hari (Walyani, 2015a).
(b) Minggu ke 5
Agar asupan kalori terpenuhi, meski mual dan
muntah, makan dalam porsi kecil tapi sering.
Konsumsi makanan memenuhi kebutuhan zat gizi
per hari pada TM I, antara lain roti, sereal, nasi 6
porsi, buah 3-4 porsi, sayuran 4 porsi, daging,
sumber protein lainnya 2-3 porsi, susu atau produk
33
olahan 3-4 porsi, camilan 2-3 porsi (Walyani,
2015a).
(c) Minggu ke 7
Konsumsi aneka jenis makanan sumber
kalsium untuk menunjang pembentukan tulang
kerangka tubuh janin yang berlangsung saat ini.
Kebutuhan kalsium anda 1000 miligram/hari
(Walyani, 2015a).
(d) Minggu ke 9
Jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan asam
folat 0,6 miligram per hari, diperbolehkan dari hati,
kacang kering, telur, brokoli, aneka produk whole
grain, jeruk dan jus jeruk. Konsumsi juga vitamin
C untuk pembentukan jaringan tubuh janin,
penyerapan zat besi, dan mencegah pre-eklamsia
(Walyani, 2015a).
(e) Minggu ke 10
Saatnya makan banya protein untuk
memperoleh asam amino bagi pembentukan otak
janin, ditambah kolin dan DHA untuk membentuk
otak baru. Sumber kolin antara pada susu, telur,
kacang-kacangan, daging sapid an roti gandum.
Sumber DHA ada pada ikan, kuning telur, produk
unggas, daging, dan minyak kanola (Walyani,
2015a).
(f) Minggu ke 12
Sejumlah vitamin yang harus dipeenuhi
kebutuhannya adalah vitamin A, B1,B2,B3 dan B6,
semuanya untuk membantu proses tumbuh
kembang, vitamin B12 untuk membentuk sel darah
baru, vitamin C untuk penyerapan zat besi, vitamin
34
D untuk pembentukan tulang dan gigi, vitamin E
untuk metabolisme (Walyani, 2015a).
(2) Kebutuhan Nutrisi pada Ibu Hamil TM II
(a) Minggu ke 13
Kurangi atau hindari minum kopi, sebab
kafeinnya (juga terdapat di teh) berisiko
menganggu perkembangan system syaraf pusat
janin yang mulai berkembang (Walyani, 2015a).
(b) Minggu ke 14
Ibu perlu menambahkan asupan 300 kalori per
hari untuk tambahan energy yang dibutuhkan untuk
tumbuh kembang janin. Penuhi antara lain dari 2
cangkir nasi atau penggantinya. Juga perlu lebih
banyak ngemil, 3-4 kali sehari porsi sedang
(Walyani, 2015a).
(c) Minggu ke 17
Makan sayur dan buah serta cairan untuk
mencegah sembelit. Penuhi kebutuhan cairan tubuh
yang meningkat. Pastikan minuman 6-8 gelas air
setiap hari. Selain itu, konsumsi sumber zat besi
(ayam, daging, kuning telur, buah kering, bayam)
dan vitamin C untuk mengoptimalkan
pembentukan sel darah merah baru, karena jantung
dan system peredaran darah janin sedang
berkembang (Walyani, 2015a).
(d) Minggu ke 24
Batasi garam, karena memicu tekanan darah
tinggi dan mencetus kaki bengkak akibat menahan
cairan tubuh. Bila ingin jajan atau makan diluar,
pilih yang bersih tidak hanya kaya karbohidrat tapi
bergizi lengkap, tidak berkadar garam dan lemak
35
tinggi (missal gorengan dan junk food). Bila
mungkin pilih yang kaya serat (Walyani, 2015a).
(e) Minggu ke 28
Konsumsi aneka jenis seafood untuk
memenuhi kebutuhan asam lemak omega-3 bagi
pembentukan otak dan kecerdasan janin. Vitamin E
sebagai antioksidan harus dipenuhi pula.
Pilihannya bayam dan buah kering (Walyani,
2015a).
(3) Kebutuhan Nutrsi Ibu Hamil Pada TM III
Ibu hamil butuh bekal energy yang memadai.
Selain untuk mengatasi beban yang kian berat, juga
sebagai cadanganenergi untuk persalinan kelak.
Pertumbuhan otak janin aka terjadi cepat sekali pada
dua bulan terakhir menjelang persalinan (Walyani,
2015a).
Berikut ini sederet zat gizi yang sebaiknya lebih
diperhatikan pada kehamilan TM III:
(a) Kalori
Kebutuhan kalori selama kehamilan adalah
sekitar 70.000-80.000 kilo kalori (kkal),dengan
berat badan sekitar 12,5 kg,. pertambahan kalori ini
diperlukan terutama pada 20 minggu terakhir.
Untuk itu tambahan kalori yang diperlukan setiap
hari adalah sekitar 285-300 kkal (Walyani, 2015a).
(b) Vitamin B6
Selain membantu metabolism asam amino,
karbohidrat, lemak dan pembentukan sel darah
merah, juga berperan dalam pembentukan
neurotransmitter. Angka kecukupan vitamin B6
bagi ibu hamil adalah sekitar 2,2 miligram sehari.
36
Makanan hewani adalah sumber yang kaya aka B6
(Walyani, 2015a).
(c) Yodium
Dibutuhkan sebagai pembentuk senyawa
tiroksi yang berperan mengontrol setiap
metabolism sel baru yang terbentuk. Bila
kekurangan senyawa ini, akibatnya proses
perkembangan janin termasuk otaknya terhambat
dan terganggu. Janin akan tumbuh kerdil.
Sebaliknya jika tiroksi berlebih, sel-sel baru
akan tumbuh secara berlebihan sehingga janin
tumbuh melampui ukuran normal. Karenanya,
cermati asupan yodium ke dalam tubuh saat hamil.
Angka yang ideal untuk konsumsi yodium adalah
175 mikrogram perhari (Walyani, 2015a).
(d) Tiamin (Vitamin B1), Riboflavin (B2) dan Niasin
(B3)
Ibu hamil dianjrkan untuk mengonsumsi
Tiamin sekitar 1,2 miligram per hari, riboflavin
sekitar 1,2 miligram perhari dan Niasin 11
miligram perhari. Ketiga vitamin B ini bisa
dikonsumsi dari keju, susu, kacang-kacang, hati
dan telur (Walyani, 2015a).
(e) Air
Kebututuhan ibu hamil di TM II ini bukan
hanya dari makanan tetapi juga dari cairan. Air
sangat penting untuk pertumbuhan sel-sel baru,
mengatur suhu tubuh, melarutkan dan mengatur
proses metabolism zat-zat gizi, serta
mempertahankan volume darah yang meningkat
selama masa kehamilan.
37
Sebaiknya minum 8 gelas air putih per hari.
Selain air putih, bisa pula dibantu dengan jus buag,
makanan berkuah dan buah-buahan (Walyani,
2015a).
c) Personal Hygiene
Adalah kebersihan yang dilakukan oleh ibu hamil untuk
mengurangi kemungkinan infeksi, karena badan yang kotor
yang banyak mengandung kuman-kuman. Kesehatan pada
ibu hamil untuk mendapatkan ibu dan anak yang sehat
dilakukan selama ibu dalam masa kehamilan. Hal ini dapat
dilakukan di antaranya dengan memperhatikan kebersihan
diri (personal Hygiene) pada ibu hamil itu sendiri, sehingga
dapat mengurangi hal-hal yang dapat memberikan efek
negative pada ibu hamil, misalnya pencegahan terhadap
infeksi (Walyani, 2015a).
d) Pakaian
Pakain yang dikenakan ibu hamil harus nyaman
tanpa sabuk/pita yang menekan dibagian perut/pergelangan
tangan, pakaian juga tidak baik terlalu ketat dileher,
stroking tungkai yang sering digunakna oleh sebagian
wanita tidak dianjurkan karena dapat menghambat sirkulasi
darah. Pakaian wanita hamil harus ringan dan menarik
karena wanita hamil tubuhnya akan bertambah besar.
Sepatu harus terasa pas, enak dan aman, sepatu bertumit
tinggi dan berujung lancip tidak baik bagi kaki, khususnya
pada saat kehamilan ketika stabilitas tubuh terganggu dan
cidera kaki yang sering terjadi (Walyani, 2015a).
38
e) Eliminasi
(1) Eliminasi pada ibu hamil
TM I: frekuensi BAK meningkat karena kadang-kadang
tertekan oleh pembesaran uterus, BAB normal
kosistensi lunak.
TM II: frekuensi BAK normal kembali karena uterus
telah keluar dari rongga panggul.
TM III: frekuensi BAK meningkat karena penurunan
kepala kek PAP (pintu atas panggul), BAB sering
obstipasi (sembelit) karena hormone progesterone
meningkat (Walyani, 2015a).
Konstipasi terjadi karena adanya pengaruh
hormone progesterone yang mempunyai efek rileks
terhadap otot polos, salah satunya otot usus. Selain itu
desakan usus oleh pembesaran janin juga menyebabkan
bertambahnya konstipasi. Tindakan pencegahan yang
dapat dilakukan adalah dengan mengonsumsi makanan
tinggi serat dan banyak minum air putih, terutama
ketika lambung dalam keadaan kososng (Walyani,
2015a).
Sering buang air kecil merupakan keluhan yang
umum dirasakan oleh ibu hamil, terutama pada
trimester I dan III. Hal tersebut adalah kondisi yang
fisiologis. Ininterjadi karena pada awal kehamilan
terjadi pembesaran uterus yang mendesak kantung
kemih sehingga kapasitasnya berkurang. Sedangkan
pada TM III terjadi pembesaran janin yang juga
menyebabkan desakan pada kantung kemih (Walyani,
2015a).
39
f) Seksual
Hubungan seksual selama kehamilan tidak dilarang
selama tidak ada riwayat penyakit seperti berikut ini:
(1) Sering abortus dan kelahiran premature.
(2) Perdarahan pervaginam.
(3) Coitus harus dilakukan dengan hati-hati terutama pada
minggu terakhir kehamilan.
(4) Bila ketuban sudah pecah, coitus dilarang karena dapat
menyebabkan infeksi janin intra uterine (Walyani,
2015a).
Bila dalam anamnesis ada abortus sebelum kehamilan
yang sekarang sebaiknya coitus ditunda sampai kehamilan
16 minggu. Pada waktu itu plasenta sudah terbentuk, serta
kemungkinan abortus menjadi lebih kecil. Pada umumnya
coitus diperbolehkan pada masa kehamilan jika dilakukan
dengan hati-hati. Pada akhir kehamilan, jika kepala sudah
masuk kedalam rongga panggul coitus sebaiknya dihentikan
karena dapat menimbulkan perasaan sakit dan perdarahan
(Walyani, 2015a).
g) Imunisasi
Imunisasi yang dibutuhkan oleh ibu hamil yang
terutama adalah tetanus toksoid. Imunisasi lain diberikan
sesuai indikasi (Walyani, 2015a).
g. Ketidaknyamanan Ibu Hamil
1) Ketidaknyamanan Pada TM I
a) Mual muntah pada pagi hari
Mual muntah terjadi pada 50% wanita hamil. Mual
kadang-kadang sampai muntah yang terjadi pada ibu hamil
biasanya terjadi pada pagi hari sehingga disebut morning
sicknes meskipun bisa juga terjadi pada siang atau sore hari.
Upaya yang dilakukan untuk mencegah atau meringankan
40
dengan melakukan beberapa hal, pada pagi hari sebelum
bangun dari tempat tidur, makan biskuit atau craskers dan
monum segelas air. Ibu hamil juga harus menghindari
makanan pedas dan berbau tajam. Ibu hamil juga dianjurkan
makan sedikit tetapi sering (Tyastuti, 2016a).
b) Pica atau ngidam
Pica atau ngidam sering terjadi pada awal trimester 1
tetapi bisa juga dialami oleh ibu hamil sampai akhir
kehamilan. Ibu hamil sering mengingingkan makanan yang
aneh-aneh, misalnya yang asam-asam, pedas-pedas.
Penyebabnya berkaitan dengan presepsi atau anggapan
individu wanita hamil tentang sesuatu yang menurutnya
bisa mengurangi rasa mual dan muntah.jadi keinginan hamil
yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda
(Tyastuti, 2016a).
c) Kelelahan atau fatique
Ibu hamil seringkali merasakan cepat lelah sehingga
kadang-kadang mengganggu aktifitas sehari-hari.
Penyebabnya yang pasti sampai saat ini belum diketauhi.
Diduga hal ini berkaitan dengan faktor metabolisme yang
rata-rata menurun pada ibu hamil. Sangat dianjurkan makan
makanan yang seimbang, tidur dan istirahat yang cukup
lakukan tidur siang. Ibu hamil harus mengatur aktivitasnya
sehari-hari untuk mendapatkan istirahat ekstra (Tyastuti,
2016a).
d) Keringat bertambah
Ibu hamil seringkali mengeluh kepanasan,
mengeluarkan keringat yang banyak. Keringat yang banyak
menyebabkan rasa tidak nyaman terkadang dapat
mengganggu tidur sehingga ibu hamil merasa lelah dan
kurang istirahat, hal ini disebabkan karena perubahan
41
hormon pada kehamilan sehingga meningkatkan aktifitas
kelenjar keringat (Tyastuti, 2016a).
e) Hidung tersumbat atau berdarah
Wanita hamil sering mengalami hidung tersumbat
seperti gejala pilek sehingga menyebabkan sulit bernapas,
ada juga yang mengalami epistaksis/hidung berdarah
(mimisan) sehingga menimbulkan kekhawatiran pada ibu
hamil. Beberapa faktor penyebab hidung tersumbat pada ibu
hamil adalah peningkatan kadar estrogen pada kehamilan
yang mengakibatkan kongesti mukosa hidung
mengeluarkan cairan berlebihan. Edema mukosa
menyebabkan hidung tersumbat, mengeluarkan cairan dan
terjadi obstruksi. Hyperemia yang terjadi pada kapiler
hidung, ditambah seringnya membuang cairan hidung dapat
menyebabkan epistaksis atau mimisan atau perdarahan
hidung (Tyastuti, 2016a).
f) Keputihan atau Leukorea
Ibu hamil sering mengeluh mengeluarkan lendir dari
vagina yang lebih banyak sehingga membuat perasaan tidak
nyaman karena celana dalam sering menjadi basah sehingga
harus sering ganti celana dalam (Tyastuti, 2016a).
Cara meringankan dan mencegah:
(1) Jaga kebersihan dengan mandi setiap hari
(2) Bersihkan alat kelamin dan keringkan setiap BAB atau
BAK.
(3) Membersihkan alat kelamin (cebok) dari arah depan ke
belakang.
(4) Ganti celana dalam apabila basah.
(5) Pakai celana dalam yang terbuat dari katun sehingga
menyerap keringat dan memberikan sirkulasi udara
yang baik
42
(6) Tidak dianjurkan memakai semprot atau douch
(Tyastuti, 2016a).
g) Sakit Kepala
Ibu hamil sering mengeluh sakit kepala, keluhan ini
bisa dirasakan ibu hamil baik trimester I, trimester II,
maupun trimester III. Faktor yang menjadi penyebab:
(1) Kelelahan atau keletihan.
(2) Spasme atau ketegangan otot.
(3) Ketegangan pada otot mata.
(4) Kongesti (akumulasi abnormal atau berlebihan cairan
tubuh).
(5) Dinamika cairan syaraf yang berubah.
2) Ketidaknyamanan pada TM II
a) Keputihan atau Leukorea
Ibu hamil sering mengeluh mengeluarkan lendir dari
vagina yang lebih banyaj sehingga membuat perasaan tidak
nyaman karena celana dalam sering menjadi basah sehingga
harus sering ganti celana dalam (Tyastuti, 2016a).
Cara meringankan dan mencegah:
(1) Jaga kebersihan dengan mandi setiap hari
(2) Bersihkan alat kelamin dan keringkan setiap BAB atau
BAK.
(3) Membersihkan alat kelamin (cebok) dari arah depan ke
belakang.
(4) Ganti celana dalam apabila basah.
(5) Pakai celana dalam yang terbuat dari katun sehingga
menyerap keringat dan memberikan sirkulasi udara
yang baik
(6) Tidak dianjurkan memakai semprot atau douch
(Tyastuti, 2016a).
43
b) Pusing
Rasa pusing sering menjadikan keluhan ibu hamil
trimester II dan trimester III. Hal ini menimbulkan rasa
ketidaknyamanan pada ibu hamil, kalau tidak ditangani
penyebabnya maka dapat mengakibatkan tekanan daah
rendah dan sampai meninggal (Tyastuti, 2016a).
c) Nyeri ligamentum rotundum
Nyeri ligamentum pada kehamilan terjadi penekanan
pada ligamentum karena uterus yang membesar.
Cara meringankan atau mencegah:
(1) Menekuk lutut kearah abdomen.
(2) Memiringkan panggul.
(3) Mandi dengan air hangat.
(4) Menggunakan korset.
(5) Tidur berbaring miring ke kiri dengan menaruh bantal
dibawah perut dan lutut (Tyastuti, 2016a).
d) Nafas sesak
Sesak nafas ini biasanya mulai terjadi pada awal
trimester II sampai pada akhir kehamilan. Ibu hamil dapat
terserang nafas sesak oleh karena pembesaran uterus dan
pergeseran organ-organ abdomen. Pembesaran uterus
membat pergeseran diafragma naik sekitar 4 cm. Ada
kalanya terjadi peningkatan hromon progesterone membuat
hyperventilasi. Ibu hamil juga harus tetap mengatur sikap
tubuh yang baik, saat berdiri tegak dengan kedua tangan
direntangkan diatas kepala kemudian menarik nafas panjang
(Tyastuti, 2016a).
e) Konstipasi atau sembelit
Konstipasi adalah BAB keras atau susah BAB biasa
terjadi pada ibu hamil trimester II dan III.
Cara mencegah atau meringankan:
44
(1) Olahraga secara teratur.
(2) Tingkatkan asupan cairan minimal 8 gelas sehari.
(3) Minum cairan panas atau sangat dingin pada saat perut
kosong.
(4) Makan sayur segar, makan bekatul 3 sendok makan
sehari, nasi beras merah.
(5) Membiasakan BAB secara teratur.
(6) Jangan menahan BAB, segera BAB ketika ada
dorongan.
(7) Perlu diperhatikan : apel segar dan kopi dapat
meningkatkan kosntipasi (Tyastuti, 2016a).
f) Varises pada kaki atau vulva
Varises pada kaki menyebabkan perasaan tidak nyaman
pada ibu hamil, biasa terjadi pada kehamilan trimester II
dan trimester III.
Cara meringankan atau mencegah:
(1) Lakukan olahraga secara teratur.
(2) Hindari duduk atau berdiri dalam jangka waktu yang
lama.
(3) Pakai sepatu dengan telapak yang berisi bantalan.
(4) Hindari memakai pakaian ketat.
(5) Berbaring dengan kaki ditinggikan.
(6) Berbaring dengan kaki bersandar di dinding (Tyastuti,
2016a).
3) Ketidaknyamanan pada TM III
a) Edema
Edema ini biasa terjadi pada kehamilan trimester II dan
trimester III. Apabila edema tidak hilang setelah bangun
tidur, edema tidak hanya terdapat di kaki tetapi juga pada
tangan dan muka, maka perlu waspada adanya preeklampsi.
Faktor penyebab:
45
(1) Pembesaran uterus pada ibu hamil mengakibatkan
tekanan pada vena pelvic sehingga menimbulkan
gangguan sirkulasi, hal ini terjadi terutama pada waktu
ibu hamil duduk atau beridri dalam waktu yang lama.
(2) Tekanan pada vena cara inferior pada saat ibu berbaring
terlentang.
(3) Kongesti sirkulasi pada ekstremitas bawah.
(4) Kadar sodium (natrium) meningkat karena pengaruh
dari hormonal. Natrium bersifat retensi cairan.
(5) Pakaian ketat.
Untuk menghindari atau mencegah sebaiknya ibu hamil
menghindari menggunakan pakaian yang ketat,
mengonsumsi makanan yang berkadar garam sangat
tinggi tidak dianjurkan. Saat bekerja atau istirahat
hindari duduk atau berdiri dalam jangka waktu yang
lama. Saat istirahat, naikkan tungkai selama 20 menit
berulang-ulang, sebaiknya ibu hamil makan-makanan
tinggi protein (Tyastuti, 2016a).
b) Pusing
Rasa pusing sering menjadikan keluhan ibu hamil
trimester II dan trimester III. Hal ini menimbulkan rasa
ketidaknyamanan pada ibu hamil, kalau tidak ditangani
penyebabnya maka dapat mengakibatkan tekanan daah
rendah dan sampai meninggal (Tyastuti, 2016a).
c) Keputihan atau Leukorea
Ibu hamil sering mengeluh mengeluarkan lendir dari
vagina yang lebih banyaj sehingga membuat perasaan tidak
nyaman karena celana dalam sering menjadi basah sehingga
harus sering ganti celana dalam (Tyastuti, 2016a).
46
d) Insomnia (sulit tidur)
Insomnia dapat tejadi biasanya dapat mulai pada
pertengahan masa kehamilan. Insomnia dapat disebabkan
oleh perubahan fisik yaitu pembesaran uterus, juga dapat
disebabkan oleh karena perubahan psikologis misalnya
persaan takut,gelisah atau kawatir karena menghadapi
persalinan. Adakalanya ditambah oleh sering BAK dimalan
hari (Tyastuti, 2016a).
e) Konstipasi atau sembelit
Konstipasi adalah BAB keras atau susah BAB biasa terjadi
pada ibu hamil trimester II dan III.
Cara mencegah atau meringankan:
(1) Olahraga secara teratur.
(2) Tingkatkan asupan cairan minimal 8 gelas sehari.
(3) Minum cairan panas atau sangat dingin pada saat perut
kosong.
(4) Makan sayur segar, makan bekatul 3 sendok makan
sehari, nasi beras merah.
(5) Membiasakan BAB secara teratur.
(6) Jangan menahan BAB, segera BAB ketika ada
dorongan.
(7) Perlu diperhatikan: apel segar dan kopi dapat
meningkatkan kosntipasi (Tyastuti, 2016a).
f) Sering buang air kecil (BAK)
Keluhan sering buang air kecil sering dialami oleh ibu
hamil trimester I dan III, hanya frekuensinya lebih sering
pada ibu hamil trimester III. Sering BAK disebabkan oleh
karena uterus membesar, yang disebabkan karena terjadi
penurunan bagian bawah janin sehingga menekan kandung
kemih. BAK juga berhubungan dengan ekskresi sodium
47
(Unsur Na) yang meningkat dan perubahan fisiologis ginjal
sehingga produksi urine meningkat.
Upaya untuk meringankan dan mencegah sering BAK, ibu
hamil dilarang untuk menahan BAK, upayakan untuk
mengosongkan kandung kemih pada saat terasa ingin BAK.
Perbanyak minum di siang hari untuk menjaga
keseimbangan dehidrasi (Tyastuti, 2016a).
g) Varises pada kaki atau vulva
Varises pada kaki menyebabkan perasaan tidak nyaman
pada ibu hamil, biasa terjadi pada kehamilan trimester II
dan trimester III.
Cara meringankan atau mencegah:
(1) Lakukan olahraga secara teratur.
(2) Hindari duduk atau berdiri dalam jangka waktu yang
lama.
(3) Pakai sepatu dengan telapak yang berisi bantalan.
(4) Hindari memakai pakaian ketat.
(5) Berbaring dengan kaki ditinggikan.
(6) Berbaring dengan kaki bersandar di dinding (Tyastuti,
2016a).
h) Mati rasa (baal), rasa perih pada jari tangan atau kaki
Mati rasa ini dapat terjadi pada kehamilan trimester II
dan trimester III. Mati rasa (baal) dapat disebabkan oleh
karena terjadinya pembesaran uterus membuat sikap/postur
ibu hamil mengalami perubahan pada titik pusat gaya berat
sehingga karena postur tersebut dapat menekan syaraf ulna
(Tyastuti, 2016a).
i) Sakit punggung
Sakit punggung pada ibu hamil terjadi pada trimester II
dan III, dapat disebabkan karena pembesaran payudara yang
dapat berakibat pada ketegangan otot, dan keletihan. Posisi
48
tubuh membungkuk ketika mengangkat barang dapat
merangsang sakit punggung, hal ini berkaitan dengan kadar
hormone yang meningkat menyebabkan cartlage pada sendi
besar menjadi lembek, di samping itu posisi tulang belakang
hiperlordosis.
Untuk meringankan atau mencegah sakit punggung ibu
hamil harus memakai BH yang dapat menopang payudara
secara benar dengan ukuran yang tepat. Hindari sikap
hiperlordosis, jangan memakai sepatu atau sandal hak
tinggi, mengupayakan tidur dengan kasur yang keras.
Hindari sikap membungkuk, tekuk lutut saat mengangkat
barang. Lakukan olah raga, senama hamil atau yoga secara
teratur (Tyastuti, 2016a).
j) Varises pada kaki atau vulva
Varises pada kaki menyebabkan perasaan tidak nyaman
pada ibu hamil, biasa terjadi pada kehamilan trimester II
dan trimester III.
Cara meringankan atau mencegah:
(1) Lakukan olahraga secara teratur.
(2) Hindari duduk atau berdiri dalam jangka waktu yang
lama.
(3) Pakai sepatu dengan telapak yang berisi bantalan.
(4) Hindari memakai pakaian ketat.
(5) Berbaring dengan kaki ditinggikan.
(6) Berbaring dengan kaki bersandar di dinding (Tyastuti,
2016a).
h. Tanda Bahaya Pada Ibu Hamil
Ada 6 tanda bahaya selama periode antenatal:
1) Perdarahan per vagina
Perdarahan tidak normal yang terjadi pada awal kehamilan
(perdarahan merah, banyak atau perdarahan dengan nyeri),
49
kemungkinan abortus, mola atau kehamilan ektopik. Perdarahan
tidak normal pada kehamilan lanjut (perdarahan merah, banyak,
kadang – kadang, tidak selalu, disertai rasa nyeri) bisa berarti
plasenta previa atau solusio plasenta (Tyastuti, 2016a)
2) Sakit kepala yang hebat, menetap yang tidak hilang
Sakit kepala hebat dan tidak hilang dengan istirahat adalah
gejala pre eklampsia (Tyastuti, 2016a)
3) Perubahan visual secara tiba – tiba (pandangan kabur)
Masalah penglihatan pada ibu hamil yang secara ringan dan
tidak mendadak kemungkinan karena pengaruh hormonal.
Tetapi kalau perubahan visual yang mendadak misalnya
pandangan kabur atau berbayang dan disertai sakit kepala
merupakan tanda pre eklampsia (Tyastuti, 2016a).
4) Nyeri abdomen yang hebat
Nyeri abdomen yang tidak ada hubungan dengan persalinan
adalah tidak normal. Nyeri yang tidak normal apabila nyeri yang
hebat, menetap dan tidak hilang setelah beristirahat, hal ini
kemungkinan karena appendisitis, kehamilan ektopik, abortus,
penyakit radang panggul, gastritis, penyakit kantung empedu,
abruptio plasenta, infeksi saluran kemih dll. (Tyastuti, 2016a).
5) Bengkak pada muka atau tangan
Hampir separuh ibu hamil mengalami bengkak normal pada
kaki yang biasanya muncul pada sore hari dan biasanya hilang
setelah beristirahat atau meninggikan kaki. Bengkak dapat
menunjukkan tanda bahaya apabila muncul pada muka dan
tangan dan tidak hilang setelah beristirahat dan disertai keluhan
fisik lain. Hal ini dapat merupakan tanda anemia, gagal jantung
atau pre eklampsia (Tyastuti, 2016a).
6) Bayi bergerak kurang dari seperti biasanya
Ibu hamil akan merasakan gerakan janin pada bulan ke 5
atau sebagian ibu merasakan gerakan janin lebih awal. Jika bayi
50
tidur gerakannya akan melemah. Bayi harus bergerak paling
sedikit 3x dalam periode 3 jam. Gerakan bayi akan lebih mudah
terasa jika ibu berbaring atau beristirahat dan jika ibu makan dan
minum dengan baik (Tyastuti, 2016a).
i. Antenatal Care (ANC)
1) Definisi Antenatal Care (ANC)
Antenatal care (ANC) merupakan asuhan pada ibu hamil
yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang meliputi fisik dan
mental untuk mendapatkan ibu dan bayi yang sehat selama masa
kehamilan, masa persalinan, dan masa nifas. Informasi tertulis
tentang perawatan kehamilan dapat dicatat pada buku kesehatan
ibu dan anak (KIA) yang penggunaannya telah dilaksanakan
(Astuti, dkk, 2017).
2) Tujuan Antenatal care (ANC)
a) Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan
kesehatan, serta kesejahteraan ibu dan janin.
b) Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik,
maternal serta sosial ibu dan bayi.
c) Mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan
selamat ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal
mungkin.
d) Mendukung dan mendorong penyesuaian psikologis dalam
kehamilan, melahirkan, menyusui, dan menjadi orangtua.
e) Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima
kelahiran bayi agar dapat tumbuh dan berkembang secara
normal.
f) Menurunkan angka kesakitan, serta kematian ibu dan
perinatal.
g) Mengenali secara dini adanya ketidaknormalan/komplikasi
yang mungkin terjadi selama masa kehamilan, termasuk
riwayat penyakit secara umum, kebidanan, dan
51
pembedahan, serta menangani atau merujuk seusia
kebutuhan.
h) Meningkatkan kesadaran sosial serta aspek psikologis
tentang melahirkan bayi dan pengaruhnya pada keluarga.
i) Memantau semua ibu hamil mengenai tanda komplikasi
obstetri secara individu dan melakukan pemeriksaan
diagnostik jika diperlukan sesuai indikasi.
j) Meyakini bahwa ibu yang mengalami tanda bahaya dapat
kembali normal setelah mendapatkan penanganan dan tidak
selalu dianggap atau diperlakukan sebagai kehamilan yang
beresiko.
k) Membangun hubungan saling percaya antara ibu dengan
pemberi asuhannya.
l) Menyediakan informasi sehingga ibu dapat membuat
keputusan berdasarkan informasi tersebut.
m) Melibatkan suami atau anggota keluarga dalam pengalaman
kehamilan yang relevan dan mendorong peran keluarga
untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan ibu.
52
Tabel 2.3 Tujuan ANC Tujuan ANC Deskripsi
Tujuan umum Untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memproleh
pelayanan antenatal yang berkualitas sehingga
mampu menjalani kehamilan dengan sehat,
bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang
sehat (Pedoman ANC terpadu Kemenkes, 2010).
Tujuan khusus Menyediakan pelayanan antenatal terpadu,
komprehensif, dan berkualitas, termasuk
konseling kesehatan dan gizi ibu hamil, serta
konseling KB dan pemberian ASI.
Memudahkan akses ANC terpadu,
komprehensif, dan berkualitas bagi ibu hamil.
Mendeteksi dini kelainan/penyakit/gangguan
yang diidap ibu hamil.
Melakukan intervensi terhadap
kelainan/penyakit/gangguan pada ibu hamil,
sedini-dininya.
Melakukan rujukan kasus ke fasilitas pelayanan
kesehatan sesuai dengan sistem rujukan yang
ada.
Sumber : Astuti dkk, 2017, Asuhan Ibu dalam Masa Kehamilan, Bagian Asuhan
Kehamilan Normal, Jakarta, halaman: 6
Pelayanan kebidanan berfokus pada upaya pencegahan,
promosi kesehatan, pertolongan persalinan normal, deteksi
komplikasi pada ibu dan anak, melaksanakan tindakan asuhan
sesuai dengan kewenangan atau bantuan lain jika diperlukan,
serta melaksanakan tindakan kegawatdaruratan.
Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan
pendidikan kesehatan, tidak hanya pada wanita, tetapi juga pada
keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini harus mencakup
pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orangtua, serta
dapat meluas pada kesehatan wanita, kesehatan seksual atau
kesehatan reproduksi, dan asuhan anak (Astuti dkk, 2017).
3) Filosofi Asuhan dalam Kehamilan
Filosofi merupakan pernyataan mengenai keyakinan dan
nilai yang dimiliki yang berpengaruh terhadap perilaku
seseorang atau kelompok. Filosofi asuhan kehamilan
menggambarkan keyakinan yang dianut oleh bidan dan
dijadikan sebagai panduan yang diyakini dalam memberikan
53
asuhan kebidanan pada klien selama masa kehamilan. Filosofi
asuhan kehamilan meliputi :
a) Wanita yang hamil normal bersifat fisiologis, bukan
patologis. Oleh karena itu, asuhan yang diberikan
merupakan asuhan yang meminimalkan intervensi. Bidan
harus memfasilitasi proses alamiah dari kehamilan dan
menghindari tindakan yang bersifat medis yang tidak
terbukti manfaatnya.
b) Asuhan kehamilan mengutamakan kesinambungan
pelayanan (continuity of care). Sangat penting bagi ibu
untuk mendapatkan pelayanan dari seorang tenaga
kesehatan profesional yang sama atau dari satu tim kecil
tenaga pofesional, karena perkembangan kondisi ibu akan
terpantau dengan baik setiap saat. Selain itu, ibu menjadi
lebih percaya dan terbuka karena merasa sudah saling
mengenal dengan tenaga kesehatan tersebut.
c) Pelayanan terpusat pada wanita (Women Centered) serta
keluarga (Family Centered). Wanita (ibu) menjadi pusat
asuhan kebidanan, yang mempunyai arti bahwa asuhan
yang diberikan harus berdasarkan pada kebutuhan ibu,
bukan kebutuhan dan kepentingan bidan. Asuhan yang
diberikan hendaknya tidak hanya melibatkan ibu hamil saja,
melainkan juga keluarganya. Hal tersebut sangat penting
bagi ibu karena keluarga menjadi bagian integral/tidak
terpisahkan dari ibu hamil.
d) Asuhan kehamilan menghargai hak ibu hamil untuk
berpartisipasi dan memperoleh pengetahuan/pengalaman
yang berhubungan dengan kehamilannya. Tenaga
profesional kesehatan tidak mungkin terus-menerus
mendampingi dan merawat ibu hamil. Oleh karena itu, ibu
hamil perlu mendapatkan informasi dan pengalaman agar
54
dapat merawat diri sendiri secara benar. Wanita harus
diberdayakan untuk mampu mengambil keputusan tentang
kesehatan diri dan keluarganya melalui tindakan
komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), serta konseling
yang dilakukan bidan (Astuti dkk, 2017).
4) Pemeriksaan Leopold
Pemeriksaan Leopold ibu hamil merupakan salah satu
komponen dari pemeriksaan abdomen pada ibu hamil. Sehingga
pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan esensial untuk
mendiagnosis kehamilan. Palpasi Leopold merupakan teknik
pemeriksaan pada perut ibu hamil untuk menentukan posisi dan
letak janin dengan melakukan palpasi abdomen pada ibu hamil.
Palpasi Leopold terdiri dari 4 langkah yaitu:
a) Leopold I
Leopold I bertujuan untuk mengetahui letak fundus uteri
dan bagian janin yang terdapat pada bagian fundus uteri.
Tabel 2.4 TFU MC. Donald Umur Kehamilan dalam Minggu Tinggi Fundus Uteri (cm)
22-28 minggu 24-25 cm diatas sympisis
28 minggu 26,7 cm diatas sympisis
30 minggu 29,5-30 cm diatas sympisis
32 minggu 29,5-30 cm diatas sympisis
34 minggu 31 cm diatas sympisis
36 minggu 32 cm diatas sympisis
38 minggu 33 cm diatas sympisis
40 minggu 33 cm diatas sympisis
Sumber: Sari, Anggita dkk. 2015. Asuhan Kebidanan pada Kehamilan
b) Leopold II
Leopold II bertujuan untuk menentukan bagian janin yang
berada pada sisi lateral maternal.
c) Leopold III
Leopold III bertujuan untuk membedakan bagian presentasi
dari janin dan memastikan apakah bagian terendah janin
masuk panggul.
55
d) Leopold IV
Leopold IV bertujuan untuk meyakinkan hasil yang
ditemukan pada pemeriksaan Leopold III dan untuk
mengetahui sejauh mana bagian presentasi sudah masuk
panggul. Pelaksanaan pemeriksaan Leopold dapat dilihat
pada gambar berikut ini:
Gambar 2.1. Pemeriksaan Leopold Sumber: Tyastuti, 2016b, Praktikum Asuhan Kebidanan Kehamilan, Bagian
Pemeriksaan Kehamilan, Jakarta, halaman 56.
Selanjutnya dari hasil pemeriksaan Palpasi Leopold ini anda
perlu menginterpretasikan hasil pemeriksaan palpasi Leopold
dari deskripsi hasil pemeriksaan dengan rabaan tangan, sehingga
Bidan mampu menentukan diagnosa tentang janin tunggal atau
ganda, umur kehamilan, letak, presentasi, punggung kanan atau
kiri yang berada pada sisi lateral, area punctum maksium untuk
auskultasi, serta menentukan sejauh mana janin masuk panggul.
Adapun mengenai deskripsi hasil pemeriksaan adalah sebagai
berikut:
a) Leopold 1: memperoleh rabaan seberapa tinggi fundus uteri
dengan rabaan jari tangan terhadap titik tunjukarea pada
56
abdomen ibu. Selanjutnya mengestimasikan umur
kehamilan berdasarkan tinggi fundus uteri. Tinggi fundus
uteri yang diperoleh dari hasil pemeriksaan Leopold 1 ini
juga dapat menjadi cross cek terhadap umur kehamilan
yang telah dihitung dari HPMT (Hari Pertama Menstruasi
Terakhir). Maka dapat ditentukan pula interpretasi terhadap
kesesuaian pertumbuhan janin terhadap usia kehamilan.
Leopold 1 juga meraba adanya bagian janin yang berada di
area fundus uteri. Deskripsi terhadap bagian janin yang
berada di area fundus uteri, apabila teraba bagian janin yang
keras, bundar dan melenting, maka interpretasinya bagian
yang berada di area fundus uteri adalah kepala, berarti
peluang letak janin memanjang dan presentasinya adalah
bokong. Biasanya kalau kepala berada di area fundus uteri,
secara subyektif ibu hamil akan mengeluh bagian diafragma
terasa lebih penuh karena terisi oleh bagian terbesar janin.
Apabila deskripsi hasil perabaan fundus uteri menunjukkan
adanya bagian janin yang kurang bundar, lunak dan tidak
melenting, maka interpretasinya adalah bagian janin yang
berada di area fundus uteri adalah bokong. Sehingga
peluangnya adalah letak memanjang presentasi kepala. Hal
ini merupakan letak dan presentasi yang normal pada
kehamilan.
b) Leopold 2: memperoleh rabaan mengenai bagian janin yang
berada pada sisi lateral (samping) kanan dan kiri ibu.
Apabila letak janin (situs) memanjang terhadap sumbu
badan ibu, maka akan teraba bagian janin yang merupakan
tahanan yang datar, keras dan memanjang pada bagian sisi
lateral kanan atau kiri ibu. Sehinggasisi lateral lain yang
berlawanan akan teraba deskripsi bagian-bagian kecil janin
baik ekstremitas tangan atau kaki, dengan deskripsi rabaan
57
menunjukkan bagian-bagian kecil dan tidak teraba tahanan.
Apabila deskripsi rabaan menunjukkan tahanan memanjang
pada sisi lateral kanan ibu, maka interpretasinya adalah
letak memanjang punggung kanan, maka bagian-bagian
kecil janin berada pada punggung kiri. Demikian pula
sebaliknya apabila deskripsi tahanan memanjang pada sisi
lateral kiri ibu, maka interpretasinya adalah letak
memanjang punggung kiri, maka bagian-bagian kecil janin
berada pada punggung kanan. Pada keadaan letak janin
melintang terhadap sumbu panjang ibu, maka pada sisi
lateral ibu akan teraba bagian yang kosong, karena bagian
punggung janin atau bagian kecil janin berada pada area
presentasi atau pada area fundus.
c) Leopold 3: memperoleh rabaan mengenai bagian janin yang
berada di area bawah uterus atau bagian terendah janin
(presentasi) dan sudah masuk panggul atau belum. Apabila
deskripsi rabaan janin menunjukkan adanya bagian yang
keras, bundar dan melenting di area bawah rahim berarti
menunjukkan interpretasi presentasi atau bagian terendah
janin adalah kepala. Berarti ini merupakan presentasi yang
normal dalam kehamilan. Apabila deskripsi
rabaanmenunjukkan adanya bagian yang lunak, kurang
bundar dan tidak melenting berarti menunjukkan
interpretasi presentasi bokong. Apabila area bawah rahim
teraba kosong, berarti peluangnya adalah letak lintang,
sehingga bagian presentasi tidak teraba adanya bagian janin.
Kemudian untuk mengetahui apakah bagian terendah janin
sudah tertangkap panggul atau apakah sudah masuk penggul
atau belum dengan cara tangan pemeriksa meraba dengan
teknik pawlik (mencekam/menangkap bagian terendah
dengan lembut, lihat gambar 1. Pemeriksaan Leopold
58
diatas), kemudian digoyangkan dengan ringan, apabila tidak
dapat digoyangkan, berarti interpretasinya adalah bagian
terendah janin sudah masuk panggul, tetapi apabila bagian
terendah janin masih bisa digoyangkan, maka
interpretasinya adalah bagian terendah janin belum masuk
panggul
d) Leopold 4: memperoleh rabaan mengenai sejauh mana
bagian terendah janin sudah masuk panggul, dengan cara
pemeriksa menghadap kaki ibu hamil, pemeriksa
membelakangi ibu hamil. Kemudian kedua telapak
tangandiletakkan secara berpasangan pada area bagian
terendah janin, dan cermati bagaimana arah kedua ujung
telapak tangan pemeriksa. Apabila perabaan kedua ujung
telapak tangan pemeriksa menunjukkan adanya konvergen
(cembung), interpretasinya adalah bagian terendah janin
sebagian besar belum masuk panggul atau sebagian kecil
saja yang masuk panggul. Apabila gambaran kedua ujung
telapak tangan menunjukkan divergen/membuka, maka
interpretasinya adalah bagian terendah janin belum masuk
panggul (Tyastuti, 2016b).
5) ANC terpadu
Ibu hamil mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan di
fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan ini dilakukan selama
rentang usia kehamilan ibu yang jenis pelayanannya
dikelompokkan sesuai usia kehamilan menjadi trimester
pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pelayanan
kesehatan ibu hamil yang diberikan harus memenuhi jenis
pelayanan sebagai berikut:
a) Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.
b) Pengukuran tekanan darah.
c) Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA).
59
d) Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).
e) Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi
tetanus sesuai status imunisasi.
f) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama
kehamilan.
g) Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ).
h) Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi
interpersonal dan konseling, termasuk KB pasca
persalinan).
i) Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes
hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan protein urin dan
pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan
sebelumnya).
j) Tatalaksana kasus sesuai indikasi (Kemenkes RI, 2019).
6) Kunjungan ANC
a) Pelayanan kesehatan ibu hamil berupa kunjungan antenatal
harus memenuhi frekuensi minimal di tiap trimester, yaitu:
(1) Minimal 1 kali pada trimester pertama (usia kehamilan
0-12 minggu).
(2) Minimal 1 kali pada trimester kedua (usia kehamilan
12-24 minggu).
(3) Minimal 2 kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24
minggu sampai menjelang persalinan) (Kemenkes RI,
2019).
b) Jadwal kunjungan ulang
(1) Kunjungan I (K1) pada TM 1 dilakukakn untuk
penapisan dan pengobatan anemia, perencanaan
persalinan, pengenalam komplikasi akibat kehamilan
dan pengobatan.
(2) Kunjungan II pada TM II dan kunjungan III pada TM
III dilakukan untuk komplikasi akibat kehamilan dan
60
pengobatan, penapisan preeklampsia, gemelli, infeksi
alat reproduksi dan saluran perkemihan, MAP (mean
arterial pressure) dan mengulang perencanaan
persalinan.
(3) Kunjungan IV (K4) pada TM III dilakukan untuk
mengenali adanya kelainan letak dan presentasi,
memantapkan rencana persalinan, mengenali tanda-
tanda persalinan (Walyani, 2015a).
7) Pemeriksaan Laboratorium pada ibu hamil
Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pada masa antenatal
menurut Astuti (2017) meliputi :
a) Pemeriksaan golongan darah
Untuk mengetahui jenis golongan darah ibu dan juga untuk
mempersiapkan calon pendnor darah sewaktu-waktu
diperlukan jika terjadi keadaan gawat darurat.
b) Pemeriksaan kadar hemoglobin (Hb)
Dilakukan minimal satu kali pada trimester I dan satu kali
pada trimester III. Pemeriksaan ini bertujuan untuk
mengetahui apakah ibu hamil menderita anemia atau tidak
selama kehamilannya.
c) Pemeriksaan protein dalam urin
Dilakukan pada trimester II dan trimester III atas indikasi.
Bertujuan untuk mengetahui adanya proteinuria pada ibu
hamil. Proteinuria adalah salah satu indikator terjadinya
preeklamsia pada ibu hamil.
d) Pemeriksaan kadar gula darah
Ibu hamil yang dicurigai mengidap diabetes mellitus harus
dilakukan pemeriksaan gula darah selama kehamilannya
minimal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada
trimester kedua, dan satu kali pada trimester ketiga
(terutama pada akhir trimester ketiga).
61
e) Pemeriksaan darah malaria
Semua ibu hamil di daerah endemis malaria menjalani
pemeriksaan darah malaria dalm upaya skrining pada
kontak pertama. Ibu hamil non-endemis malaria menjalani
pemeriksaan darah malaria jika terdapat indikasi.
f) Pemeriksaan tes sifilis
Dilakukan di daerah dengan risiko tinggi dan pada ibu
hamil yang diduga sifilis. Pemeriksaan sifilis sebaiknya
dilakukan sedini mungkin pada kehamilan.
g) Pemeriksaan HIV
Ditujukan untuk daerah dengan risiko tinggi kasus HIV dan
ibu hamil yang dicurigai mengidap HIV.
h) Pemeriksaan BTA (Basil Tahan Asam)
Dilakukan pada ibu hamil yang dicurigai mengidap
tuberculosis sebagai pencegahan agar infeksi tuberculosis
tidak mempengaruhi kesehatan janin.
i) Pemeriksaan HbSAg
Diambil dari darah vena, dilakukan pada pemeriksaan hamil
yang pertama, bertujuan untuk mengetahui ada atau
tidaknya virus hepatitis B dalam darah, baik dalam kondisi
aktif maupun sebagai carier (Marmi, 2014).
j. Continuity Of Care (COC)
Bidan merupakan penyedia utama dalam asuhan pada wanita
pada sebagia besar negara didunia. Sesuai filosofi bidan, asuhan
berpusat pasa wanita (women-centered care) pada pelayanan
kesehatan primer yang bergantung pada hubungan antara bidan dan
wanita selama daur kehidupan. Model asuhan bidan merupakan
normalitas, asuhan berkesinambungan (COC), dan dirawat oleh
bidan yang telah dikenal dan dipercaya selama persalinan.
COC merupakan bagian dari filosofi kehidupan. Continuity of
care mempunyai arti bahwa seorang wanita mengembangkan
62
kemitraan dengan bian untuk menerima asuhan selama masa
kehamilan,masa persalinan,dan masa nifas. Continuity of care
memastikan ibu dan bayi mendapatkan asuhan yang terbaik dari
bidan pada seluruh periode kehamilan dan melahirkan. Hasil satu
studi menemukan bahwa COC dapat mengurangi intervensi obstetric
selama persalinan dan tidak ada kematian ibu sesuai dengan tujuan
MDGs 4 dan MDGs 5 yaitu menurunkan AKI dan AKB. Asuhan
yang berkesinambungan mengakui bahwa melahirkan yang aman
sangat penting untuk kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak.
Continuity of care merupakan hal yang mendasar dan model
praktik kebidanan untuk memberikan asuhan holistik, membangun
kemitraan yang berkelanjutan untuk memberikan dukungan, dan
membina hubungan saling percaya antara bidan dan klien.
Continuity of care dapat diberikan melalui tim bidan yang
berbagai beban kasus, yang bertujuan untuk memastikan bahwa ibu
menerima semua asuhannya dari satu bidan atau tim praktiknya.
Bidan dapat bekerja sama secara multidisiplin dalam melakukan
konsultasi dan rujukan dengan tenaga kesehatan lainnya. Menurut
WHO, dimensi pertama dari Continuity of care yaitu dimulai dari
prakehamilan, selama kehamilan, persalinan, serta hari-har awal dan
tahun kehidupan. Dimensi kedua dari Continuity of care yaitu tempat
pelaynan yang berhubungan dengan berbagai tingkat pelayanan dari
rumah, masyarakat, dan sarana kesehatan (Astuti, dkk 2017).
k. KSPR (Kartu Score Poedji Rochjati)
1) Pengertian
Kartu Skor Poedji Rochjati (KSPR) yaitu berupa kartu skor
yang digunakan sebagai alat skrining antenatal berbasis keluarga
guna menemukan factor risiko ibu hamil, yang selanjutnya
dilakukan upaya terpadu untuk menghindari dan mencegah
kemungkinan terjadinya upaya komplikasi obstetric pada saat
persalinan (Hastuti dkk, 2018).
63
2) Tujuan KSPR
Membuat pengelompokkan dari ibu hamil Kehamilan
Resiko Rendah (KRR), Kehamilan Resiko Tinggi (KRT),
Kehamilan Resiko Sangat Tinggi (KRST), agar berkembang
perilaku kebutuhan tempat dan penolong persalinan sesuai
dengan kondisi dari ibu hamil dan melakukan pemberdayaan ibu
hamil, suami, keluarga dan masyarakat agar peduli dan
memberikan dukungan dan bantuan kesiapan mental, biaya dan
transportasi untuk melakukan rujukan terencana (Hastuti dkk,
2018).
3) Fungsi KSPR
Fungsi dari KSPR menurut Wijaya (2019) adalah:
a) Melakukan skrining deteksi dini ibu hamil risiko tinggi.
b) Memantau kondisi ibu dan janin selama kehamilan.
c) Memberi pedoman penyuluhan untuk persalinan aman
berencana (Komunikasi Informasi Edukasi/KIE).
d) Mencatat dan melaporkan keadaan kehamilan, persalinan,
dan nifas.
e) Validasi data mengenai perawatan ibu selama kehamilan,
persalinan, nifas dengan kondisi ibu dan bayinya.
f) Audit Maternal Perinatal (AMP)
4) Pengelompokan KSPR
Kelompok risiko menurut Rohjati dalam Wijaya (2019),
dibagi menjadi 3 yaitu:
a) Kehamilan Risiko Rendah (KRR) : Skor 2(hijau)
b) Kehamilan Risiko Tinggi (KRT) : Skor 6-10 (kuning)
c) Kehamilan Risiko Sangat Tinggi (KRST) : Skor ≥ 12
(merah)
Perencanaan persalinan pada ibu hamil dengan skor 6 atau
lebih : dianjurkan bersalin dengan tenaga kesehatan. Ibu hamil
64
dengan skor 12 atau lebih : dianjurkan bersalin di rumah sakit
atau dengan spesialis kandungan (Sp.OG) (Hastuti dkk, 2018).
Terdapat 20 faktor risiko yang dibagi menjadi 3 kelompok
faktor risiko pada penilaian KSPR yaitu:
a) Kelompok Faktor Risiko I
Yaitu Kehamilan Risiko Rendah (KRR) atau Ada
Potensi Gawat Obstetrik (APGO) yaitu ibu tidak
mempunyai keluhan dan selama kehamilan ibu dalam
keadaan sehat dan biasanya ditemukan dengan mudah
melalui pemeriksaan sederhana yaitu wawancara dan
pemeriksaan oleh tenaga kesehatan. Untuk ibu hamil
dengan kehamilan risiko rendah jumlah skor 2 yaitu tanpa
adanya masalah atau faktor risiko. Persalinan dengan
kehamilan risiko rendah dalam dilakukan secara normal
dengan keadaan ibu dan bayi sehat, tidak dirujuk dan dapat
ditolong oleh bidan. Terdapat sepuluh faktor risiko yaitu
tujuh terlalu dan tiga pernah meliputi :
(1) Primi Muda yaitu ibu yang pertama hamil terlalu muda
≤16 tahun. Wanita berumur ≤16 tahundimana pada usia
tersebut reproduksi belum siap dalam menerima
kehamilan kondisi rahim dan panggul yang masih kecil,
akibat dari ini janin mengalami gangguan sehingga
dapat meningkatkan risiko perdarahan antepartum,
perdarahan postpartum, dan bayi prematur. Risiko
terjadi gangguan kesehatan lebih besar pada waktu usia
muda.
(2) Primi tua yaitu lama perkawinan ≥4 tahun. Primi tua
lama perkawinan >4 tahun atau lebih dengan kehidupan
perkawinan biasa pasangan suami istri tinggal serumah,
tidak memakai alat kontrasepsi (KB), serta suami istri
tidak sering keluar kota
65
(3) Primi Tua pada Umur Ibu ≥35 tahun yaitu ibu hamil
pertama pada umur ≥35 tahun. Bahaya yang dapat
terjadi yaitu mengalami preeklampsi, ketuban pecah
dini, persalinan macet, perdarahan setelah persalinan,
bayi dengan berat badan lahir rendah <2500 g.
(4) Anak Terkecil Umur <2 tahun yaitu ibu hamil yang
jarak kelahiran dengan anak terakhir kurang dari 2
tahun. Kesehatan fisik dan rahim ibu masih belum pulih
dengan sempurna. Bahaya yang dapat terjadi yaitu
perdarahan setelah bayi lahir karena kondisiibu masih
lemah, bayi prematur, bayi dengan berat badan lahir
rendah <2500 g.
(5) Primi tua sekunder yaitu ibu hamil dengan persalinan
terakhir 10 tahun yang lalu. Ibu dalam kehamilan dan
persalinan ini seolah-olah menhadapi persalinan yang
pertama lagi.
(6) Grande Multi yaitu ibu pernah hamil atau melahirkan
lebih dari empat kali. Kemungkinan yang akan ditemui
karena ibu sering melahirkan yaitu keadaan kesehatan
yang terganggu seperti kurang gizi, anemia, dan
kekendoran dinding rahim. Bahaya yang dapat timbul
yaitu persalinan letak lintang, kelainan letak, dan
persalinan lama.
(7) Usia ibu terlalu tua (>35 tahun) yaitu kondisi dimana
pada usia ini organ kandungan menua yang ditandai
dengan perubahan pada jaringan alat-alat kandungan
dan jalan lahir tidak lentur lagi sehingga pada
umumnya proses melahirkan dilakukan sesar.
(8) Tinggi badan <145 cm yaitu keadaan ibu dengan tinggi
badan 145 cm atau kurang (terlalu pendek). Ibu dengan
tinggi badan 145 cm meningkatkan risiko mengalami
66
penyulit dalam persalinan. Tinggi badan ibu
mencerminkan ukuran pelvis yang berhubungan dengan
distosia.
(9) Riwayat Obstetri Jelek (ROJ) yaitu kondisi yang terjadi
pada kehamilan kedua, dimana kehamilan yang
pertama mengalami keguguran, lahir mati, lahir belum
cukup bulan, dan lahir hidup lalu mati umur 7 hari.
Bahaya yang terjadi yaitu kegagalan kehamilan dapat
terjadi berulang dengan tanda-tanda pengeluaran buah
kehamilan sebelum waktunyakeluar dan perut terasa
kencang.
(10) Persalinan Yang Lalu Dengan Tindakan, yaitu
persalinan yang ditolong dengan alat melalui jalan lahir
biasa atau per vaginam yaitu tindakan dengan tarikan
cunam/ forsep atau vakum. Bahaya yang terjadi yaitu
robekan atau perlukaan pada jalan lahir dan perdarahan
pasca persalinan.
(11) Bekas Operasi Sesar yaitu ibu hamil yang melakukan
persalinan dengan operasi sesar. Akibat operasi sesar
terbentuk bekas luka pada dinding rahim yang
merupakan jaringan kaku dan ada kemungkinan mudah
robek pada persalinan berikutinya yang disebut robekan
rahim.
b) Kelompok Faktor Risiko II
Yaitu Ada Gawat Obstetrik (AGO) atau kelompok
Kehamilan Risiko Tinggi (KRT) dengan jumlah skor 6 -10,
adanya satu atau lebih penyebab masalah pada kehamilan,
baik dari pihak ibu maupun bayi dalam kandungan yang
memberi dampak kurang menguntungkan baik bagi ibu atau
calon bayi. Kategori KRT memiliki risiko kegawatan tetapi
tidak daruratini kebanyakan terjadi pada umur kehamilan
67
enam bulan atau lebih. Untuk mendapat kepastian
dibutuhkan pemeriksaan alat USG oleh dokter spesialis.
Terdapat beberapa penyakit pada ibu hamil yang tergolong
pada faktor risiko kelompok dua yaitu :
(1) Anemia dalam kehamilan yaitu kondisi ibu dimana
kadar hemoglobin dibawah 11g% pada trimester 1 dan
3 atau kadar <10.5g% pada trimester 2. Ibu hamil
dengan anemia dapat menimbulkan penyulit-penyulit
yaitu keguguran, kelahiran prematur, persalinan lama,
perdarahan pasca melahirkan karena atonia uteri.
(2) Penyakit jantung dalam kehamilan harus mendapatkan
perhatian ekstra.Apabila terjadi kehamilan pada ibu
hamil dengan penyakit jantung dianjurkan untuk
melakukan terminasi.
(3) Diabetes mellitus yaitu suatu kondisi dimana tubuh
tidak dapat menghasilkan insulin dalam jumlah yang
memadai atau tubuh kurang bisa memaksimalkan
penggunaan insulin. Penyakit ini bisa munculsaat hamil
atau ibu memang penderita penyakit ini.
(4) Penyakit infeksi yang sering terjadi selama kehamilan
yaitu infeksi saluran kemih kemungkinan hal ini dapat
terjadi yaitu karena uterus yang membesar sehingga
memperlambat aliran air kemih yang dapat
menyebabkan bakteri tidak bisa dibuang.
(5) Penyakit asma pada kehamilan dapat menghambat
pertumbuhan janin dalam kandungan atau memicu
terjadinya persalinan prematur.
(6) Penyakit Malaria sering dijumpai pada kehamilan
trimester I dan III dan merupakan infeksi parasit yang
disebabkan plasmodiumyang ditemukan dalam darah.
Komplikasi yang dapat terjadi adalah abortus, berat
68
badan lahir rendah , penyulit partus dan gangguan
fungsi ginjal.
(7) Preeklampsi ringan yaitu hipertensi yang timbul setelah
20 minggu kehamilan. Ditandai dengan edema,
pembengkakan pada tungkai atau muka. Bahaya yang
dapat terjadi yaitu preeklampsia berat dan kemudian
timbul serangan kejang-kejang yang disebut eklampsia.
(8) Hamil kembar (gemelli), kehamilan kembar berisiko
lebih tinggi terjadi partus prematur dan anemia pada ibu
hamil sehingga disarankan untuk melakukan
pemeriksaan darah secara berkala pada minggu ke-20,
minggu ke-24 dan minggu ke-28.
(9) Hidramnion yaitu keadaan dimana keadaan jumlah air
ketuban melebihi batas normal. Batas normal air
ketuban berjumlah 1-2 liter sedangkan pada hidramnion
air ketuban melebihi batas 2 liter yaitu antara 4-5 liter.
(10) Janin mati dalam rahim, ditandai dengan keluhan -
keluhan dari ibu hamil yaitu tidak terasa gerakan janin,
perut terasa mengecil, dan payudara mengecil. Hamil
seorotinus yaitu kehamilan yang belum terjadi
persalinan melewati 42 minggu atau 294 hari.
(11) Kehamilan dengan kelainan letak dibagi menjadi
duayaitu letak lintang dan letak sungsang. Pada letak
lintang, bahu berada diatas pintu panggul sedangkan
kepala terletak di salah satu fosa iliaka dan bokong
berada pada fosa iliaka yang lain. Sedangkan letak
sungsang adalah keadaan dimana letak janin
memanjang dengan posisikepala di fundus uteri dengan
presentasi bokong.
69
c) Kelompok Faktor Risiko III
Yaitu Ada Gawat Darurat Obstetrik(AGDO)atau
kelompok kehamilan risiko sangat tinggi (KRST) dengan
jumlah skor ≥12. Ibu hamil dengan dua atau lebih faktor
risiko meningkat dan memerlukan ketepatan waktu dalam
melakukan tindakan rujukan serta pertolongan persalinan
yang memadai di rumah sakit ditanganioleh dokter
spesialis.Pada keadaan ini ibuhamil harus segera dirujuk ke
rumah sakit sebelum kondisi ibu dan janin semakin parah.
Faktor risiko pada kelompok ini adalah:
(1) Perdarahan Antepartum yaitu perdarahan pada trimester
terakhir dari kehamilan yaitu setelah minggu ke-28
masa kehamilan. Perdarahan antepartum dibagi menjadi
dua yaitu plasenta previa dan solusio plasenta. Plasenta
previa adalah plasenta yang berimplantasi rendah
sehingga menutupi sebagian/seluruh ostium uteri
internum sedangkan solusio plasenta adalah terlepasnya
sebgaian atau seluruh permukaan maternal plasenta dari
tempat implantasinya
(2) Preeklampsia berat ditandai dengan tekanan darah >110
mmHg disertai proteinuria dan atau disertai edema pada
kehamilan 20 minggu atau lebih. Sedangkan eklampsia
adalah kasus akut penderita preeklampsi yang disertai
dengan adanya kejang menyeluruh dan
koma.Preeklampsia dan eklampsia merupakan indikasi
dari persalinan tindakan seksio sesaria.
70
Gambar 2.2 Kartu Skor Poedji Rochjati Sumber: Kemenkes RI. 2010. Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu
l. Indeks Massa Tubuh (IMT)
Peningkatan berat badan optimal untuk rata-rata kehamilan
adalah 12,5 kg, 9 kg diperoleh pada 20 minggu terakhir. BB yang
optimal ini berkaitan dengan resiko komplikasi terendah selama
kehamilan dan persalinan serta BBLR. Peningkatan BB yang tepat
setiap ibu hamil saat ini didasarkan pada indeks masa tubuh
prekehamilan (body mass index) yang menggambarkan
71
perbandingan berat badannya lebih sedikit daripada ibu yang
memasuki kehamilan denga BB sehat (Walyani, 2015).
Perhitungan berat badan berdasarkan indeks massa tubuh:
IMT = BB/(TB)²
dimana : IMT = Indeks massa tubuh
BB = Berat badan (kg)
TB = Tinggi badan (m)
Tabel 2.5 IMT KATEGORI IMT REKOMENDASI
Rendah <19,8 12,5 – 18
Normal 19,8 – 26 11,5 – 16
Tinggi 26 – 29 7 – 11,5
Obesitas >29 ≥7
Gemeli 16-20,5
Sumber: Walyani, 2015, Asuhan Kebidanan pada Kehamilan, Bagian Perubahan
Anatomi, Yogyakarta, halaman: 58
m. Menentukan Tafsiran Persalinan
Tafsiran persalinan dihitung dengan menggunakan rumus yang
disebut aturan Naegele. Untuk menggunakan rumus ini, digunakan
hari pertama haid terakhir (HPHT) ibu, yaitu tanggal ditambah 7 hari
kemudian bulan dikurangi 3 dan tahun ditambah 1 (Astuti ddk,
2017).
2. Konsep Dasar Asuhan Kebidanan Kehamilan
a. Pengkajian data
Pada langkah pertama ini dikumpullkan semua informasi yang
akurat dari semua yang berkaitan dengan kondisi klien. Untuk
memperoleh data dapat dilakukan dengan cara anamnesa,
pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan dan pemeriksaan tanda-
tanda vital, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan penunjang.
Langkah ini merupakan langkah awal yang akan menentukan
langkah berikutnya, sehingga kelengkapan data sesuai dengan kasus
yang dihadapi akan menentukan proses interpretasi yang benar atau
tidak dalam tahap selnajutnya, sehingga dalam pendekatan ini harus
yang komprehensif meliputi data subjektif, objektiif dan hasil
72
pemeriksaan sehingga dapat menggambarkan kondisi/masalah klien
yang sebenarnya (Walyani, 2015).
1) Data Subyektif
a) Biodata
(1) Nama
Mengetahui nama klien dan suami berguna untuk
memperlancar komunikasi dalam asuhan sehingga tidak
terlihat kaku dan lebih akrab (Walyani, 2015).
(2) Umur
Umur perlu diketahui guna mengetahui apakah klien
dalam kehamilan yang beresiko atau tidak. Usia di
bawah 16 tahun dan di atas 35 tahun merupakan umur-
umur yang beresiko tinggi untuk hamil. Umur yang
baik untuk kehamilan maupun persalinan adalah 19-35
tahun (Walyani, 2015).
(3) Suku/Bangsa/Etnis/Keturunan
Ras, etnis, dan keturunan harus diidentifikasi dalam
rangka memberikan perawatan yang peka budaya
kepada klien dan mengidentifikasi wanita atau keluarga
yang memiliki kondisi resesif otosom dengan insiden
yang tinggi pada populasi tertentu. Jika kondisi yang
demikian diidentifikasi, wanita tersebut diwajibkan
menjalani skrining genetik (Walyani, 2015).
(4) Agama
Tanyakan pilihan agama klien dan berbagai praktik
terkait agama yang harus diobservasi. Informasi ini
dapat menuntun ke suatu diskusi tentang pentingnya
agama dalam kehidupan klien, tradisi keagamaan dalam
kehamilan dan kelahiran, perasaan tentang jenis
kelamin tenaga kesehatan, dan pada beberapa kasus,
penggunaan produk darah (Walyani, 2015).
73
(5) Pendidikan, Minat, Hobi
Tanyakan pendidikan tertinggi yang klien tamatkan
juga minat, hobi, dan tuuan jangka panjang. Informasi
ini membantu klinis memahami klien sebagai individu
dan memberi gambaran kemampuan baca-tulisnya.
Kadang-kadang bahaya potensial dari hobi, seperti
melukis, memahat, mengelas, membuat mebel, piloting,
balap, menembak, stained glass, membuat keramik, dan
berkebun akan diidentifikasi. Materi yang akan
digunakan dalam kegiatan seni dan kerajinan tangan
dapat mengandung silikon, talek, pelarut, dan logam
berat. Semua ini berpotensi membahayakan (Walyani,
2015).
(6) Pekerjaan
Mengetahui pekerjaan klien adalah penting untuk
mengetahui apakah klien berada dalam keadaan utuh
dan untuk mengkaji potensi kelahiran, prematur dan
pajanan terhadap bahaya lingkungan kerja, yang dapat
merusak janin (Walyani, 2015).
(7) Alamat bekerja
Alamat bekerja klien perlu diketahui juga sebagai
pelengkap identitas diri klien (Walyani, 2015).
(8) Alamat rumah
Alamat rumah klien perlu diketahui bidan untuk lebih
memudahkan saat pertolongan persalinan dan untuk
mengetahui jarak rumah dengan tempat rujukan
(Walyani, 2015).
(9) No. RMK (Nomor Rekam Medik)
Nomor rekam medik biasanya digunakan di Rumah
Sakit, Puskesmas, atau Klinik (Walyani, 2015).
74
b) Menanyakan keluhan utama klien (KU)
Keluhan utama adalah alasan kenapa klien datang ke tempat
bidan. Hal ini disebut tanda atau gejala. Dituliskan sesuai
dengan yang diungkapkan oleh klien serta tanyakan juga
sejak kapan hal tersebut dikeluhkan oleh klien.
Mendengar keluhan klien sangat penting untuk
pemeriksaan. Pertanyaan yang sangat sederhana seperti
“Untuk apa Nyonya datang kemari?” atau “Apa keluhan
Anda?” dapat memberikan keterangan banyak ke arah
diagnosis. Misalnya apakah wanita mengatakan bahwa ia
mengeluarkan darah dari kemaluannya setelah haid
terlambat, bahwa peranakannya turun/keluar, bahwa ia
mengalami perdarahan tidak teratur atau berbau busuk,
maka dalam hal-hal demikian kiranya tidak sulit untuk
menduga kelainan apa yang sedang dihadapi oleh bidan,
yaitu berturut-turut abortus, prolapsus uteri dan serviks
uteri. Namun, pemeriksaan lebih lanjut tetap harus
dilakukan karena diagnosis tidak boleh berdasarkan atas
anamnesis semata (Walyani, 2015).
c) Menanyakan Riwayat Kehamilan Sekarang, yang meliputi:
(1) Menarche (Usia pertama datang haid)
(2) Siklus, Siklus haid terhitung mulai hari pertama haid
hingga hari pertama haid berikutnya.
(3) Lamanya, Lamanya haid yang normal adalah +7 hari.
(4) Banyaknya, Normalnya yaitu 2 kali ganti pembalut
dalam sehari.
(5) Dismenorhoe (Nyeri haid)
(6) Riwayat Hamil Sekarang
(7) HPHT (Hari Pertama Haid Terakhir)
(8) TP (Taksiran Persalinan)/Perkiraan Kelahiran
(9) Kehamilan yang ke-
75
(10) Masalah-masalah
(11) TM I : tanyakan pada klien apakah klien ada masalah
seperti : hiperemesis gravidarum, anemia, dan lain-lain.
(12) TM II : tanyakan pada klien apa yang pernah ia rasakan
pada trimester II kehamilan pada kehamilan
sebelumnya.
(13) TM III : tanyakan pada klien apa yang pernah ia
rasakan pada trimester III kehamilan pada kehamilan
sebelumnya.
(14) ANC (Antenatal Care/Asuhan Kehamilan)
(15) Tempat ANC
(16) Penggunaan obat-obatan
(17) Imunisasi TT
(18) Penyuluhan yang didapat
d) Menanyakan Riwayat Kehamilan Lalu, yang meliputi:
(1) Jumlah kehamilan (Graviid/G)
(2) Jumlah anak yang hidup (L)
(3) Jumlah kelahiran prematur (P)
(4) Jumlah keguguran (A)
(5) Persalinan dengan tindakan (operasi sesar, vakum,
forsep)
(6) Riwayat perdarahan pada persalinan atau pasca
persalinanKehamilan dengan tekanan darah tinggi
(7) Berat bayi < 2,5 atau 4 kg
(8) Masalah lain, setiap komplikasi yang terkait dengan
kehamilan harus diketahui sehingga dapat dilakukan
antisipasi terhadap komplikasi berulang. Sebagai
contoh, kehamilan ektopik cenderung berulang.
e) Menanyakan Riwayat Kesehatan, yang meliputi:
(1) Riwayat kesehatan ibu
(a) Penyakit yang pernah diderita
76
(b) Penyakit yang sedang diderita
(c) Apakah pernah dirawat
(d) Berapa lama dirawat
(e) Dengan penyakit apa dirawat
(2) Riwayat kesehatan keluarga
(a) Riwayat menular
(b) Riwayat menurun
f) Menanyakan riwayat Sosial Ekonomi, meliputi:
(1) Status pernikahan
(a) Menikah
(b) Usia saat menikah
(c) Lama pernikahan
(d) Dengan suami sekarang
(e) Isteri keberapa dengan suami sekarang
g) Riwayat KB
(1) Metode
(2) Lama
(3) Masalah
h) Kebiasaan hidup sehat
(1) Pola nutrisi, meliputi: jenis makanan, porsi, frekuensi,
pantangan, alasan pantang
(2) Personal hygiene, meliputi: frekwensi mandi, frekwensi
gosok gigi, frekwensi ganti pakaian, kebersihan vulva
i) Pola aktifitas
j) Pola eliminasi
(1) BAB meliputi: frekwensi, warna dan masalah
(2) BAK, meliputi: frekwensi, warna, bau dan masalah
k) Menanyakan temapt untuk persalinan
Tempat yang diinginkan klien sebagai tempat persalinan
perlu ditanyakan karena untuk memperkirakan layak
tidaknya tempat yang diinginkan klien tersebut.
77
l) Menanyakan petugas untuk persalinan
Petugas persalinan yang diinginkan klien perlu ditanyakan
karena untuk memberikan pandangan kepada klien tentang
perbedaan asuhan persalinan yang akan didapatkan antara
dokter kandungan, bidan dan dukun beranak.
m) Menanyakan Data Psikologis, yang meliputi:
(1) Respon ibu hamil terhadap persalinan, yang meliputi:
siap untuk kehamilan dan siap menjadi ibu, lama
didambakan, salah satu tujuan perkawinan.
(2) Respon suami terhadap kehamilan, Apabila respon
suami klien terlihat kurang bahagia menyambut
kehamilan klien, maka bidan harus pintar
mempengaruhi suami klien agar bisa menerima
kehamilan istrinya tersebut dengan kebahagiaan.
(3) Dukungan keluarga lain terhadap kehamilan, tanyakan
bagaimana respon dan dukungan keluarga lain misalnya
anak (apabila telah mempunyai anak), orang tua, serta
mertua klien.
(4) Pengambilan keputusan
Pengambilan keputusan perlu ditanyakan karena untuk
mengetahui siapa yang diberi kewenangan klien
mengambil keputusan apabila ternyata bidan
mendiagnosa adanya keadaan patologis bagi kondisi
kehamilan klien yang memerlukan adanya penanganan
serius.
n) Menanyakan data spiritual, klienperlu ditanyakan apakah
keadaan rohaninya saat itu sedang baik ataukah sedang
strees karena suatu masalah
o) Menanyakan data social budaya, yang meliputi: tradisi yang
mempengaruhi kehamilan, kebiasaan yang merugikan
kehamilan
78
2) Data Objektif
a) Pemeriksaan umum
(1) Keadaan umum dan kesadaran penderita
Compos mentis (kesadaran baik), gangguan kesadaran
(apatis, samnolen, spoor, koma).
(2) Tekanan Darah
Tekanan darah yang normal adalah 110/180 mmHg
sampai 140/190 mmHg, hati-hati adanya
hipertensi/preeklamsi (Walyani, 2015).
(3) Nadi
Nadi normal adalahm 60 sampai 100 menit. Bila
abnormal mungkin ada kelainan paru-paru atau jantung
(Walyani, 2015).
(4) Suhu badan
Suhu badan normal adalah 36,50C sampai 37,5
0C. Bila
suhu lebih tinggi dari 37,50C kemungkinan ada infeksi
(Walyani, 2015).
(5) Tinggi badan
Diukur dalam cm, tanpa sepatu. Tinggi badan kurang
dari 145 cm ada kemungkinan terjadi Cepalo Pelvic
Disproposian (CPD) (Walyani, 2015).
(6) Berat badan
Berat badan yang bertambah terlalu besar atau kurang,
perlu mendapatkan perhatian khusus karena
kemungkinan terjadi penyulit kehamilan. Kenaikan
berat badan tidak boleh dari 0,5 kg per minggu
(Walyani, 2015).
79
b) Pemeriksaan fisik
(1) Inspeksi
(a) Muka
Periksa palpebra, konjungtiva, dan sklera. Periksa
palpebra untuk memeriksa oedema umum. Periksa
konjungtiva dan sclera untuk memperkirakan
adanya anemia dan ikterus.
(b) Mulut/gigi
Periksa adanya karies, tonsillitas dan faringitis. Hal
tersebut merupakan sumber infeksi.
(c) Jantung
Infeksi bila tampak sesak, kemungkinan ada
kelainan jantung yang dapat meningkatkan
terjadinya resiko yang lebih tinggi baik bagi ibu
maupun bayinya.
(d) Payudara
Inspeksi bentuk payudara, benjolan, pigmentasi
putting susu. Palpasi adanya benjolan (tumor
mamae) dan colostrums.
(e) Abdomen
Inspeksi pembesaran perut (bila pembesaran perut
itu berlebihan kemungkinan asites, tumor, ileus,
dan lain-lain), pigmentasi di linea alba, nampakkah
gerakan anak atau kontraksi rahim, adakah strie
gravidarum atau luka bekas operasi.
(f) Tangan dan tungkai
Inspeksi pada tibia dan jari untuk melihat adanya
oedema dan varices. Bila terjadi oedema pada
tempat-tempat tersebut kemungkinan terjadinya
pre-eklamsia.
80
(g) Vulva
Inspeksi untuk mengetahui adanya oedema,
varices, keputihan, perdarahan, luka, ciran yang
keluar, dan sebagainya.
(2) Palpasi
Palpasi yaitu pemeriksaan kebidanan pada abdomen
dengan menggunakan manuver leopold untuk
mengetahui keadaan janin didalam abdomen.
(a) Leopold I
Untuk mengetahui fundus uteri dan bagian yang
berada pada bagian fundus dan mengukur tinggi
fundus uteri dari simfisis untuk menentukan usia
kehamilan dengan menggunakan (kalau > 12
minggu) atau cara Mc. Donald dengan pita ukuran
(kalau > 22 minggu).
(b) Leopold 2
Untuk mengetahui letak janin memanjang atau
melintang, dan bagian janin yang teraba disebelah
kiri atau kanan.
(c) Leopold 3
Untuk menentukan bagian janin yang ada di bawah
(presentasi).
(d) Leopold 4
Untuk menentukan apakah bagian janin sudah
masuk panggul atau belum (Walyani, 2015).
(3) Auskultasi
Auskultasi dengan menggunakan stetoskop monoaural
atau doopler untuk menentukan DJJ setelah umur
kehamilan 18 minggu, yang meliputi frekuensi,
keteraturan, dan kekuatan DJJ. DJJ normal adalah 120
sampai 160 per menit. Bila DJJ < 120 atau > 160 per
81
menit, maka kemungkinan ada kelainan janin atau
plasenta (Walyani, 2015).
(4) Perkusi
Melakukan pengetukan pada daerah patella untuk
memastikan adanya refleks pada ibu (Walyani, 2015).
c) Pemeriksaan Dalam/Pemeriksaan Khusus
Pemeriksaan dalam dilakukan oleh dokter/bidan pada usia
kehamilan 34 sampai 36 minggu untuk primmigravida atau
40 minggu pada multigravida dengan janin besar.
Pemeriksaan ini untuk mengetahui keadaan serviks, ukuran
panggul, dan sebagainya.
d) Pemeriksaan Penunjang
(1) Pemeriksaan Laboratorium
Melakukan tes laboratorium yang diperlukan yakni
protein urine, glukosa urine, dan hemoglobin.
(2) Pemeriksaan Ultrasonografi (Walyani, 2015).
b. Menyusun diagnosa
Pada langkah ini bidan mengidentifikasi masalah atau diagnosa
potensial berdasarkan rangkaian masalah atau diagnosa yang sudah
diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila
memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengawasi pasien
bidan bersiap-siap bila masalah potensial benar-benar terjadi
(Walyani, 2015). Mengantisipasi perlunya tindakan segera oleh
bidan dan/dokter untuk konsultasi atau ditangani bersama dengan
anggota tim kesehatan lain (Walyani, 2015).
c. Merencanakan Asuhan kebidanan
Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang
sudah teridentifikasi dari kondisi/masalah klien, tapi juga dari
kerangka pedoman antisipasi terhadap klien tersebut, apakah
kebutuhan perlu konseling, penyuluhan dan apakah pasien perlu
dirujuk karena ada masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah
82
kesehatan lain. Pada langkah ini tugas bidan adalah merumuskan
rencana asuhan sesuai dengan hasil pembahasan rencana bersama
klien dan keluarga, kemudian membuat kesepakatan bersama
sebelum melaksanakannya (Walyani, 2015).
d. Melaksanakan asuhan kebidanan
Pada langkah ini rencana asuhan yang komperhensif yang telah
dibuat dapat dilaksanakan secara efisien seluruhnya oleh bidan atau
dokter atau tim kesehatan lain (Walyani, 2015).
e. Evaluasi
Melakukan evaluasi hasil dari asuhan yang telah diberikan meliputi
pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah
terpenuhi sesuai dengan diagnosa/masalah (Walyani, 2015).
f. Dokumentasi SOAP
Model dokumentasi yang digunakan dalam asuhan kebidanan yaitu
dalam bentuk catatan perkembangan karena bentuk asuhan yang
diberikan berkesinambungan dan menggunakan proses yang terus
menerus dengan menggunakan subjektif, objektif, analisis, dan
penatalaksanaan (SOAP) yang merupakan salah satu metode
pendokumentasian.
1) S = Subjektif
Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data
klien melalui anamnesis antara lain tanggal, tahun, waktu,
biodata, riwayat, termasuk kondisi klien. Catatan data spesifik
atau fokus. Tanda dan gejala subjektif yang didapatkan dari
hasil bertanya pada klien, suami dan keluarga. Catatan ini
berhubungan dengan masalah sudut pandang klien. Ekspresi
klien mengenai kekhawatiran dan keluhannya dicatat sebagai
kutipan langsung atau ringkasan yang berhubungan dengan
diagnosa.
83
2) O = Objektif
Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data
klien melalui pengamatan dan terukur, pemeriksaan fisik klien
didapatkan melalui inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi,
termasuk data penunjang. Data ini memberikan bukti gejala
klinis klien dan fakta yang berhubungan dengan diagnosa.
3) A = Analisis
Menggambarkan pendokumentasian hasil analisis, diagnosis,
dan masalah kebidanan.
4) P = Penatalaksanaan
Mencatat seluruh perencanaan dan penatalaksanaan yang telah
dilakukan, misalnya tindakan antisipatif, tindakan segera,
tindakan secara komprehensif, penyuluhan, dukungan,
kolaborasi, evaluasi/follow up dan rujukan. Dokumentasi
menunjukkan perencanaan yang tepat (Astuti dkk, 2017).
B. Persalinan
1. Konsep Dasar Persalinan
a. Pengertian
Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput
ketuban keluar dari uterus ibu. Perslinan dikatakan normal jika
prosesnya terjadi pada kehamilan cukup bulan (usia 37 minggu)
tanpa disertai penyulit. Persalinan dimulai (inpartu) sejak uterus
berkontraksi dan menyebabkan perubahan pada serviks
(membuka dan menipis) dan berakhir dengan lahirnya plasenta
secara lengkap. Ibu belum dapat dikategorikan in partu jika
kontraksi uterus tidak mengakibatkan perubahan atau
pembukaan (JNPK-KR, 2017).
84
b. Sebab Terjadinya Persalinan
1) Adanya kontraksi rahim
Secara umum, tanda awal bahwa ibu hamil untuk
melahirkan adalah mengejangnya rahim atau dikenal
dengan istilah kontraksi. Kontraksi tersebut berirama,
teratur, dan involuter, umumnya kontraksi bertujuan untuk
menyiapkan mulut lahir untuk membesar dan meningkatkan
aliran darah di plasenta. Setiap kontraksi uterus memiliki
tiga fase yaitu:
a) Increment : ketika intensitas terbentuk
b) Acme : puncak atau maksimum
c) Decement : ketika otot relaksasi
Kontraksi yang sesungguhnya akan muncul dan hilang
secara teratur dengan intensitas makin lama makin
meningkat. Peut akan mengalami kontraksi dan relaksasi,
diakhir kehamilan proses kontraksi akan lebih sering terjadi
(Walyani dan Purwoastuti, 2015).
Kontraksi uterus memiliki periode relaksasi yang
memiliki fungsi penting untuk mengistirahatkan otot uterus,
memberi kesempatan istirahat bagi wanita, dan
mempertahankan kesejahteraan bayi karena kontraksi uterus
menyebabkan kontraksi pembuluh darah plasenta. Durasi
kontraksi uterus sangat bervariasi, tergantung pada kala
persalinan wanita tersebut. Kontraksi pada persalinan aktif
berlangsung dari 45 sampai 90 detik dengan durasi rata-rata
60 detik. Pada persalinan awal, kontraksi mungkin hanya
berlangsung 15 sampai 20 detik (Walyani dan Purwoastuti,
2015).
2. Keluarnya lendir bercampur darah
Lendir disekresi sebagai hasil proliferasi kelenjar lendir
servik pada awal kehamilan. Lendir mulanya menyumbat
85
leher rahim, sumbatan yang tebal pada mulut rahim
terlepas, sehingga menyebabkan keluarnya lendir yang
berwarna kemerahan bercampur darah dan terdorong keluar
oleh kontraksi yang membuka mulut rahim yang
menandakan bahwa mulut rahim menjadi lunak dan
membuka (Walyani dan Purwoastuti, 2015).
3. Keluarnya air-air (ketuban)
Proses penting menjelang persalinan adalah pecahnya air
ketuban. Keluarnya air dan jumlahnya cukup banyak,
berasal dari ketuban yang pecah akibat kontraksi yang
makin sering terjadi. Ketuban mulai pecah sewaktu-waktu
sampai pada saat persalinan. Ketika ketuban sudah mulai
pecah, maka sudah saatnya bayi harus keluar.bila ibu hamil
merasakan ada cairan yang merembes keluar dari vagina
dan keluarnya tidak dapat ditahan lagi, tetapi tidak disertai
mulas atau tanpa sakit, merupakan tanda ketuban pecah
dini, yakni ketuban pecah sebelum terdapat tanda-tanda
persalinan, sesudah itu akan terasa sakit karena ada
kemungkinan kontraksi. Normalnya air ketuban ialah cairan
yang bersih, jernih, dan tidak berbau (Walyani dan
Purwoastuti, 2015).
4. Pembukaan servik
Penipisan mendahului dilatasi servik, pertama-tama
aktivitas uterus dimulai untuk mencapai penipisan, setelah
penipisan kemudian aktivitas uterus menghasilkan dilatasi
servik yang cepat. Membukanya leher rahim sebagai respon
terhadap kontraksi yang berkembang. Tanda ini tidak
dirasakan oleh pasien tetapi dapat diketahui dengan
pemeriksaan dalam. Servik menjadi matang selama periode
yang berbeda-beda sebelum persalinan, kematangan servik
86
mengindikasikan kesiapanya untuk persalinan (Walyani dan
Purwoastuti, 2015).
c. Macam-Macam Persalinan
1) Persalinan spontan yaitu persalinan yang berlangsung dengan
kekuatan ibu sendiri ,melalui jalan lahir tersebut.
2) Persalinan buatan, bila persalinan dibantu dengan tenaga dari
luar misalnya ekstraksi forcep, atau dilakukan operasi section
caesaria.
3) Persalianan anjuran, persalinan yang tidak dimulai dengan
sendirinya tetapi baru berlangsung setelah pemecahan
ketuban, pemberian Pitocin atau prostlaglandin (Kurniarum,
2016).
d. Faktor Yang Mempengaruhi Persalinan
1) Passage (Jalan Lahir)
Jalan lahir dibagi atas :
a) Bagian keras tulang-tulang panggul (rangka panggul)
b) Bagian lunak: otot-otot, jaringan-jaringan, ligamen-
ligament.
Ukuran-ukuran panggul :
a) Alat pengukur ukuran panggul:
(1) Pita meter
(2) Jangka panggul : martin, oseander, collin, dan
baudelokue
(3) Pelvimetri klinis dengan periksa dalam
(4) Pelvimetri rongenologis
b) Ukuran-ukuran panggul :
(1) Distansia spinarum: jarak antara kedua spina iliaka
anterior superior 24-26 cm
(2) Distansia kristarum: jarak antara kedua krista iliaka
kanan dan kiri 28-30 cm
(3) Konjungata eksterna: 18-20 cm
87
(4) Lingkar panggul: 80-100 cm
(5) Conjugate diagonalis: 12,5 cm
(6) Distansia tuberum: 10,5 cm
(7) Ukuran dalam panggul:
(a) Pintu atas panggul merupakan suatu bidang
yang di bentuk oleh promontorim, linea
innuminata dan pinggir atas simpisis pubis.
(b) Konjungata vera: dengan periksa dalam di
peroleh konjungata diagonalis 10,5 cm
(c) Konjungata tranversa: 12-13 cm
(d) Konjungata obligua: 13 cm
(e) Konjugata obstetrika adalah jarak bagian
tengah simfisis ke promontorium.
(f) Ruang tengah panggul.
(g) Bidang terluas ukurannya 13 x 12,5 cm.
(h) Bidang tersempit ukurannya 11,5 x 11 cm.
(i) Jarak antara spina isciadika 11 cm.
(j) Pintu bawah panggul (outlet).
(k) Ukuran anterior-posterior 10-12 cm.
(l) Ukuran melintang 10,5 cm.
(m) Arcus pubis membentuk sudut 90 derajat lebih
(Walyani dan Purwoastuti, 2015)
2) Power (His dan Mengejan)
Kekuatan yang mendorong janin dalam persalinan adalah
his, kontraksi oto-otot perut, kontraksi diafragma, dan aksi
dari ligament.
a) His (kontraksi uterus)
His adalah gelombang kontraksi ritmis otot polos
dinding uterus yang dimulai dari daerah fundus uteri
dimana tuba falopi memasuki dinding uterus, awal
gelombang tersebut di dapat dari “pacemaker” yang
88
terdapat dari dinding uterus daerah tersebut. His
memiliki sifat:
(1) Involutir
(2) Intermiten
(3) Terasa sakit
(4) Terkoordinasi
(5) Serta kadang dipengaruhi oleh fisik, kimia, psikis
Perubahan-perubahan akibat his:
(1) Pada uterus dan servik: uterus teraba keras/padat
karena kontraksi. Tekanan hidrostatis air ketuban
dan tekanan intrauteri naik serta menyebabkan
servik menjadi mendatar (affecement) dan terbuka
(dilatasi).
(2) Pada ibu: rasa nyeri karena iskemia rahim dan
kontraksi uterus. Juga ada kenaikan nadi dan
tekanan darah.
(3) Pada janin: pertukaran oksigen pada sirkulasi utero
plasenta kurang, maka timbul hipoksia janin.
Pembagian his dan sifatnya:
(1) His palsu atau pendahuluan
(a) His tidak kuat, tidak teratur
(b) Dilatasi servik tidak terjadi
(2) His pembukaan kala I
(a) His pembukaan servik sampai terjadi
pembukaan lengkap 10.
(b) Mulai makin, teratur dan sakit
(3) His pengeluaran atau his mengejan (kala II)
(a) Sangat kuat, teratur simetris, terkoordinasi dan
lama
(b) His untuk mengeluarkan janin
89
(c) Koordinasi bersama antara: his kontraksi otot
perut, kontraksi difragma dan ligament
(4) His pelepasan uri (kala III)
Kontraksi sedang untuk melepaskan dan
melahirkan plasenta
(5) His pengiring (kala IV)
Kontraksi lemah, masih sedikit nyeri (meriang)
pengecilan rahim dalam beberapa jam atau hari
b) Mengejan
Dalam proses persalinan normal ada 3 komponen
yang amat menentukan, yakni passenger (janin),
passage (jalan lahir), dan power (kontraksi). Agar
proses persalinan berjalan lancar, ketiga komponen
tersebut harus sama-sama dalam kondisi baik. Bayi
yang ukurannya tidak terlalu besar pasti lebih mudah
melalui jalan lahir nirmal, jalan lahir yang baik akan
memudahkan bayi keluar, kekuatan ibu mengejan akan
mendorong bayi cepat keluar (Walyani dan
Purwoastuti, 2015).
3) Passengger
Passengger terdiri dari:
a) Janin
Selama janin dan plasenta berada dalam rahim
belum tentu pertumbuhannya normal, adanya kelainan
genetik dan kebiasaan ibu yang buruk dapat
menjadikan pertumbuhannya tidak normal antara lain:
(1) Kelainan bentuk dan besar janin: anensefalus,
hidrosefalus, janin makrosomia.
(2) Kelainan pada letak kepala: presentasi puncak,
presentasi muka, presentasi dahi dan kelainan
oksiput.
90
(3) Kelainan letak janin: letak sungsang, letak lintang,
letak mengolak, presentasi rangkap (kepala,
tangan, kepala kaki, kepala tali pusat).
b) Plasenta
Plasenta berbentuk bundar atau oval, ukuran
diameter 15-20 cm, tebal 2-3 cm, dan berat 500-600
gram. Plasenta biasanya terlepas 4-5 menit setelah anak
lahir, mungkin pelepasan setelah anak lahir. Juga
selaput janin menebal dan berlipat-lipat karena
pengecilan dinding rahim. Oleh kontraksi dan retraksi
rahim rahim terlepas karena tarikan waktu plasenta
lahir.
c) Air ketuban
Sebagai cairan pelindung dalam pertumbuhan dan
perkembangan janin. Air ketuban berfungsi sebagai
bantalan untuk melindungi janin terhadap trauma dari
luar. Tak hanya itu saja, air ketuban juga berfungsi
melindungi janin dari infeksi, menstabilkan perubahan
suhu, dan menjadi sarana yang memungkinkan janin
bergerak bebas. Saat usia kehamilan mulai memasuki
25 minggu, rata-rata air ketuban didalam rahim 239 ml,
yang kemudian meningkat menjadi 984 ml pada usia
kehamilan 33 minggu (Walyani dan Purwoastuti,
2015).
4) Psikologi
Perubahan psikologi pada saat persalinan yaitu
peningkatan rasa cemas, yang akan mengakibatkan
peningkatan rasa nyeri, terutama pada ibu primigravida
yang belum mempunyai bayangan mengenai kejadia-
kejadian selama proses persalinan. Oleh sebab itu penting
sekali mempersiapkan mental ibu karena pada saat
91
persalinan akan mengganggu pembukaan dan membuat ibu
lama sembuh (Sondakh, 2013).
5) Penolong
Penolong persalinan adalah seseorang yang memiliki
pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk membantu ibu
dalam menjalankan proses persalinan. Faktor penolong ini
memegang peranan penting dalam membantu ibu bersalin
karena mempengaruhi kelangsungan ibu dan bayi (Sondakh,
2013).
e. Perubahan Fisiologi pada Ibu Bersalin
Sejumlah perubahan fisiologis yang normal akan terjadi selama
persalinan, hal ini bertujuan untuk mengetahui perubahan-perubahan
yang dapat dilihat secara klinis bertujuan untuk secara tepat dan cepat
menginterpretasikan tanda gejala tertentu dan penemuan perubahan
fisik serta laboratorium apakah normal atau tidak (Walyani, 2015a).
1) Perubahan fisiologis kala I
a) Perubahan Tekanan Darah
Perubahan darah meningkat selama kontraksi uterus dengan
kenaikan sistolik rata-rata 10-20 mmHg dan kenaikan distolik
rata-rata 5-10 mmHg diantara kontraksi-kontraksi uterus,
tekanan darah akan turun seperti sebelum masuk persalinan
dan akan kembali naik lagi bila terjadi kontraksi (Walyani,
2015a).
b) Perubahan metabolism
Selama persalinan baik metabolisme karbohidrat aerobic
maupun anaerobic akan naik secara perlahan. Kenaikan ini
sebagian besar diakibatkan karena kecemasan serta kegiatan
otot rangka tubuh. Kegiatan metabolisme yang meningkat
tercemin dengan kenaikan suhu tubuh, denyut nadi,
pernafasan, kardiak output dan kehilangan cairan (Walyani,
2015a).
92
c) Perubahan suhu tubuh
Suhu badan akan sedikit meningkat selama persalinan. Suhu
mencapai tertinggi selama persalina dan segera setelah
persalinan. Kenaikan dianggap normal asal tidak melebihi 0,5-
1 derajat Celsius. Suhu badan yang sedikit naik ini wajar, dan
mengindikasikan ibu dehidrasi. Parameter lainnya yang harus
dilakukan yaitu selaput ketuban pecah atau belum, karena hal
ini merupakan tanda infeksi (Walyani, 2015a).
d) Denyut jantung
Penurunan yang menyolok selama acme konstraksi uterus
tidak terjadi jika ibu berada dalam posisi miring bukan posisi
rerlentang. Denyut jantung di antara konstraksi sedikit lebih
tinggi dibanding selama periode persalinan atau belum masuk
persalinan. Denyut jantung yang sedikit naik merupakan hal
yang normal,meskipun normal perlu dikontrol secara periode
untuk mengidentifikasi infeksi (Walyani, 2015a).
e) Pernafasan
Kenaikan pernafasan dapat disebabkan karena adanya rasa
nyeri,kekhawatiran serta penggunaan tehnik pernafasan yang
tidak benar (Walyani, 2015a).
f) Perubahan renal
Polyuri sering terjadi selama persalinan,hal ini disebabkan oleh
kardiak output yang meningkat serta glomelurus serta aliran
plasma ke renal. Protein dalam urine (+1) selama persalinan
merupakan yang wajar, tetapi proteinuri (+2) merupakan hal
wajar,keadaan ini lebih sering pada ibu
primipara,anemia,persalinan lama atau pada kasus hal yang
tidak pre ekslamsia (Walyani, 2015a).
g) Perubahan Gastrointestinal
Kemampuan pergerakan gastrik serta penyerapan makanan
padat berkurang akan menyebabkan pencernaan hampir
93
berhenti selama persalinan dan akan menyeba abkan konstipasi
(Walyani, 2015a).
h) Perubahan hematologis
Haemoglobin akan meningkat 1,2gr/100ml selama persalinan
dan kembali ketingkat pra persalinan pada hari sel-sel darah
putih meningkat secara progessif selama kala satu persalinan
sebesar 5000s/d 15.000 WBC sampai dengan akhir pembukaan
lengkap,hal ini tidak berindikasi adanya infeksi. Gula darah
akan turun selama dan akan turun secara menyolok pada
persalinan yang mengalami penyulit atau persalinan lama
(Walyani, 2015a).
i) Konstraksi Uterus
Konstraksi uterus terjadi karena adanya rangsangan pada otot
polos uterus dan penurunan hormon progesteron yang
menyebabkan keluarnya hormon oksitosin (Walyani, 2015a).
j) Pembentukan segmen atas rahim dan segmen bawah rahim
Segmen Atas Rahim (SAR) terbentuk pada uterus bagian atas
dengan sifat otot yang lebih tebal dan kontraktif,terdapat
banyak otot sorong dan memanjang. SAR terbentuk dari
fundus sampai ishimus uteri Segmen Bawah Rahim (SBR)
terbentang di uterus bagian bawah antara ishimus dengan
serviks dengan sifat otot yang tipis dan elastis,pada bagian ini
banyak terdapat otot yang melingkar dan memanjang
(Walyani, 2015a).
k) Perkembangan Retraksi Ring
Retraksi ring adalah batas pinggiran antara SAR dan SBR,
dalam keadaan persalinan normal tidak tampak dan akan
kelihatan pada persalinan obnormal,karena konstraksi uterus
yang berlebihan,retraksi ring akan tampak sebagai garis atau
batas yang menonjol di atas simpisis yang merupakan tanda
dan ancaman ruptur uterus (Walyani, 2015a).
94
l) Penarikan serviks
Pada akhir kehamilan otot yang mengelilingi Ostium Uteri
Internum (OUI) ditarik oleh SAR yang menyebabkan serviks
menjadi pendek dan menjadi bagian dari SBR. Bentuk serviks
menghilang karena canalis servikalis membesar dan
membentuk Ostium Uteri Eksterna (OUE) sebagai ujung
menjadi sempit. dan bentuknya menjadi sempit (Walyani,
2015a).
m) Pembukaan ostium oteri interna dan ostiun oteri exsterna
Pembukaan serviks disebabbkan karena membesarnya OUE
karena otot yang melingkar disekitar ostium meregang untuk
dapat dilewati kepala. Pembukaan uteri tidak saja terjadi
karena penarikan SAR akan tetapi karena tekanan isi uterus
yaitu kepala dan kantong amnion. Pada primigravida dimulai
dari ostium uteri internum terbuka lebih dahulu baru ostium
eksterna membuka pada saat persalinan terjadi. Sedangkan
pada multi gravida ostium uteri internum dan eksternum
membuka secara bersama-sama pada saat persalinan terjadi
(Walyani, 2015a).
n) Show
Adalah pengeluaran dari vagina yang terdiri dan sedikit lendir
yang bercampur darah, lendir ini berasal dari ekstruksi lendir
yang menyumbat canalis servikalis sepanjang
kehamilan,sedangkan darah berasal dari desidua vera yang
lepas (Walyani, 2015a).
o) Tonjolan kantong ketuban
Tonjolan kantong ketuban ini disebabbkan oleh adanya
regangan SBR yang menyebabkan terlepasnya selaput korion
yang menempel pada uterus,dengan adanya tekanan maka akan
terlihat kantong yang berisi caiaran yang menonjol ke ostium
uteri internum yang terbuka. Cairan ini terbagi dua yaitu fore
95
water dan hind water yang berfungsi melindungi selaput
amnion agar tidak terlepa seluruhnya. Tekanan yang diarahkan
ke cairan sama dengan tekanan ke uterus sehingga akan timbul
generasi floud presur (Walyani, 2015a).
p) Pemecahan kantong ketuban
Pada akhir kala satu bila pembukaan sudah lengkap dan tidak
ada tahanan lagi,ditambah dengan konstraksi yang kuat serta
desakan janin yang menyebabkan kantong ketuban
pecah,diikuti dengan proses kelahiran bayi (Walyani, 2015a).
2) Perubahan Fisiologis pada Kala II Persalinan
a) Kontraksi Uterus
Dimana kontraksi ini bersifat nyeri yang disebabkan oleh
anoxia dari sel-sel otot tekanan pada ganglia dalam serviks dan
Segmen Bawah Rahim (SBR), regangan dari serviks, regangan
dan tarikan pada peritoneum, itu semua terjadi pada saat
kontraksi. Adapun kontraksi bersifat berkala dan Sue harus di
perhatikan adalah lamanya kontraksi berlangsung 60-90 detik,
kekuatan kontraksi, kekuatan kontraksi secara klinis ditentukan
dengan mencoba apakah jari kita dapat menekan dinding rahim
ke dalam, interfal antara kedua kontraksi pada kala
pengeluaran sekali dalam 2 menit (Walyani, 2015a).
b) Perubahan-perubahan Uterus
Keadaan Seggmen Atas Rahim (SAR) dan Segmen Bawah
Rahim (SBR). Dalam persalinan perbedaan SAR dan SBR
akan tampak lebii jelas, dimana SAR dibentuk oleh korpus
uteri dan bersifat menmegalng peranan aktif (berkontraksi) dan
dindingnya bertambah tebal debgan majunya persalinan,
dengan kata lain SAR mengadakan suatu kontraksi menjadi
tebal dan mendorong anak keluar. Sedangkan SBR dibentuk
oleh isthimus uteri yan sifatnya memegang peranan pasif dan
makin tipis dengan majunya persalinan (disebabkan karena
96
regangan), dengan kata lain SBR dan serviks menngadakan
relaksasi dan dilatasi (Walyani, 2015a).
c) Perubahan pada Serviks
Perubahan pada serviks pada kala II ditandai dengan
pembukaan lengkap, pada pemeriksaan dalam tidak teraba lagi
bibir portio, Segmen Bawah Rahim (SBR), dan serviks
(Walyani, 2015a).
d) Perubahan pada Vagina dan Dasar Panggul
Setelah pembukaan lengkap dan ketuban telah pecah terjadi
perubahan, terutama pada dasar panggul yang diregangkan
oleh bagian depan janin sehingga menjadi saluran yang
dinding-dindingnya tipis karena suatu regangan dan kepala
sampai di vulva, lubang vulva menghadap ke depan atas dan
anus, menjadi terbuka, perineum menonjol dan tidak lama
kemudian kepala janin tampak pada vulva (Walyani, 2015a).
e) Perubahan Fisik Lain yang Mengalami Perubahan
(1) Perubahan Sistem Reproduksi
Kontraksi uterus pada persalinan bersifat unik mengingat
kontraksi ini merupakan kontraksi otot fisiologisyang
menimbulkan nyeri pada tubuh. Selama kehamilan terjadi
keseimbangan antara kadar progesterone kehamilan kadar
minggu sebelum uterus. Kontraksi utrus mula-mula jarang
dan tidak teratur dengan intensitasnya ringan, kemudian
menjadi lebih sering, lebih lama dan intensitasnya semakin
kuat seiring kemajuan persalinan. dan di dalam darah,
tetapi pada akhir estrogen dan progesterone menurun kira-
kira 1-2 dimulai sehingga menimbulkan kontraksi uterus
(Walyani, 2015a).
(2) Perubahan Tekanan Darah
Tekanan drah akan meningkat selama kontraksi disertai
peningkatan sistolik rata-rata 10-20 mmHg. Pada waktu-
97
waktu di antara kontraksi tekanan darah kembali ke
tingkat sebelum persalinan. Dengan mengubah posisi
tubuh dari telentang ke posisi miring, perubahan tekanan
darah selama kontraksi dapat dihindari. Nyeri, rasa takut
dan kekhawatiran dapat semakin meningkatkan tekanan
darah (Walyani, 2015a).
(3) Perubahan Metabolisme
Selama persalinan, metabolisme karbohidratt meningkar
dengan kecepatan tetap. Peningkatan ini terutama
disebabkan oleh aktifitas otot. Peningkatan aktifitas
metabolic telihat dari peningkatan suhu tubuh, denyut
nadi, pernapasan, denyut jantung dan cairan yang hilang
(Walyani, 2015a).
(4) Perubahan Suhu
Perubahan suhu sedikit meningkat selama persalinan dan
tertinggi selama dan segera setelah melahirkan. Perubahan
suhu di anggap normalbila peningkatan suhu yang tidak
lebih dari 0,5-l0C yang mencerminkan peningkatan
metabolisme selama persalinan (Walyani, 2015a).
(5) Perubahan Denyut Nadi
Perubahan yang mencolok selama kontraksi disertai
peningkatan selama fase peningkatan, penurunan selama
titik puncak sampai frekuensi yang lebih rendah daripada
frekuensi di antarakontraksi dan peningkatan selamafase
penurunan hingga mencapai frekuensi lazim di antara
kontraksi. Frekuensi denyut nadi di antara kontraksi
sedikit lebih meningkat disbanding selama periode
menjelang persalinan (Walyani, 2015a).
(6) Perubahan Pernafasan
Peningkatan frekuensi pernapasan normal selama
persalinan dan mencerminkan peningkatan metabolisme
98
yang terjaur. Hiperventelasi yang menunjang adalah
temuan abnormal dan dapat menyebabkan alkalosis (rasa
kesemutan pada ekstremie dan perasaan pusing) (Walyani,
2015a).
(7) Perubahan pada Ginjal
Poliuria sering terjadi selama persalinan. Kondisi ini dapat
di akibatkan peningkatan lebih lanjut curah jantung selama
persalinan dan kemungkinan peningkatan laju filtrasi
glomelurus dan aliran plasma ginjal. Poliura menjadi
kurang jelas pada posisi velentang karena posisi ini
membuat aliran urine berkurang selama persalinan
(Walyani, 2015a).
(8) Perubahan pada Saluran Cerna
Absorbsi lambung terhadap makanan padat jauh lebih
berkurang. Apabila kondisi ini diperburuk oleh lanjut
sekresi asam lambung selama persalinan, maka saluran
cerna bekerja dengan lambat sehingga waktu penosongan
lambungg menjadi lebih lama. Oleh karena itu, wanita
harus di anjurkan untuk tidak makan dalam porsi besar
atau minum berlebihan, tetapi makan dan minum ketika
keinginan timbulguna mempertahankan energi dan hidrasi.
(Walyani, 2015a).
(9) Perubahan Hematologi
Hemoglobin meningkat rata-rata 1,2 gr/100 ml selama
persalinan dan kembali ke kadar sebelum persalinan pada
hari, pertama pascapartum jika tidak ada kehilangan darah
yang abnormal. Waktu koagulasi darah berkurang dan
terdapat peningkatan fibrinogen plasma lebih lanjut
selama persalinan (Walyani, 2015a).
99
f. Perubahan Psikologis pada Ibu Bersalin
1) Perubahan psikologis kala 1 yang sering terjadi:
a) Kecemasan dan ketakutan pada dosa-dosa atau kesalahan-
kesalahan sendiri. Ketakutan tersebut berupa rasa takut jika
bayi yang dilahirkan dalam keadaan cacat, serta takhayul lain.
Walaupun pada jaman ini kepercayaan-kepercayaan pada
ketakutan-ketakutan ghaib selama proses reproduksi sudah
sangat berkurang sebab secara biologis, anatomis dan fisiologis
kesulitan-kesulitan pada masa partus bisa di jelaskan dengan
alasan-alasan patologis atau sebab abnormalitas (keluar
biasaan). Tetapi masih ada perempuan yang diliputi rasa
ketakutan.
b) Timbul rasa tegang, takut, kesakitan, kecemasan dan konflik
batin.Hal ini disebabkan oleh semakin membesarnya janin
dalam kandungan yang mengakibatkan calon ibu mudah capek,
tidak nyaman badan, dan tidak bisa tidur nyenyak, sering
kesulitan bernapas, dan macam-macam beban jasmaniah
lainnya.
c) Sering timbul rasa jengkel, tidak nyaman serta selalu kegerahan
serta tidak sabar (kepala bayi sudah memasuki panggul dan
timbulnya kontraksi pada rahim, sehingga sehingga bayi yg di
harapkan, kini menjadi beban berat)
d) Ketakutan menghadapi resiko dan kesulitan bahaya melahirkan
bayi yang merupakan hambatan dalam proses persalinan
(1) adanya rasa takut gelisah singkat tanpa sebab
(2) sesak napas atau rasa tercekik
(3) jantung berdebar-debar
(4) takut mati
(5) merasa tidak tertolong, muka pucat, pandangan liar
(6) napas pendek,takikardi
100
e) Adanya harapan-harapan mengenai jenis kelamin bayi yang
akan dilahirkan(harapan cinta kasih, implus bermusuhan dan
kebencian)
f) Sikap bermusuhan terhadap bayinya (keinginan memiliki bayi
yang unggul, belum mampu menjadi seorang ibu, cemas kalau
bayinya tidak aman diluar rahim)
g) Kegelisahan dan ketakutan menjelang kelahiran bayi (takut
mati, trauma kelahiran, perasaan bersalah, ketakutan riil)
2) Perubahan psikologis pada kala II
a) Panik dan takut terhadap apa yang terjadi pada saat pembukaan
lengkap
b) Bingung dengan apa yang terjadi saat pembukaan lengkap
c) Frustasi dan marah
d) Tidak memperdulikan apa saja dan siapa saja yang ada di
kamar bersalin
e) Rasa lelah dan sulit mengikuti perintah
f) Fokus pada dirinya sendiri
3) Perubahan psikologis pada kala III
a) Bahagia
Karena saat-saat yang lama telah di tunggu akhirnya datang
juga, yaitu kelahiran bayinya. dan ibu juga merasa bahagia
karena merasa sudah menjadi wanita yang sempurna (bisa
melahirkan, memberikan anak untuk suaminya dan
memberikan anggota keluarga yang baru), bahagia karena bisa
melihat anaknya.
b) Cemas dan takut
Cemas dan takut jika ada bahaya atas dirinya saat
persalinan karena persalinan di anggap sebagai suatu keadaan
antara hidup dan mati. Cemas dan takut dengan pengalaman
yang lalu,takut tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya.
101
4) Perubahan psikologis pada kala IV
a) Phase honeymoon
Phase honeymoon adalah phase setelah anak lahir dimana
terjadi intimasi dan kontak yang lama antara ibu, ayah dan
anak. Hal ini dapat dikatakan sebagai psikis honeymoon yang
tidak memerlukan hal-hal yang romantik. Masing-masing
saling memperhatikan anaknya dan menciptakan hubungan
yang baru.
b) Ikatan kasih
Terjadi pada kala IV di mana diadakan kontak antara ibu-
ayah-anak, dalam ikatan kasih. Penting bagi bidan memikirkan
bagaimana agar hal tersebut dapat terlaksana, partisipasi suami
dalam proses persalinan merupakan salah satu upaya untuk
proses ikatan kasih tersebut (Legawati, 2018).
g. Tahapan Persalinan
Proses persalinan di bagi 4 kala yaitu :
1) Kala I : Kala Pembukaan
Waktu untuk pembukaan serviks sampai menjadi pembukaan
lengkap (10 cm). Dalam kala pembukaan dibagi menjadi 2 fase:
a) Fase Laten
Dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan
dan pembukaan serviks secara bertahap.
(1) Pembukaan kurang dari 4 cm
(2) Biasanya berlangsung kurang dari 8 jam.
b) Fase Aktif
(1) Frekuensi dan lama kontraksi uterus umumnya
meningkat (kontraksi adekuat/3 kali atau lebih dalam
10 menit dan berlangsung selama 40 detik atau lebih)
(2) Serviks membuka dari 4 ke 10, biasanya dengan
kecepatan 1 cm/lebih perjam hingga pembukaan
lengkap (10)
102
(3) Terjadi penurunan bagian terbawah janin
(4) Berlangsung selama 6 jam dan di bagi atas 3 fase,
yaitu;
Berdasarkan kurva friedman:
(1) Periode akselerasi, berlangsung selama 2 jam
pembukaan menjadi 4 cm
(2) Periode dilatasi maksimal, berlangsung selama 2 jam
pembukaan berlangsung cepat dari 4 menjadi 9 cm
(3) Periode diselerasi, berlangsung lambat dalam waktu 2
jam pembukaan 9 cm menjadi 10 cm/lengkap
2) Kala II: Kala Pengeluaran Janin
Waktu uterus dengan kekuatan his ditambah kekuatan
mengejan mendorong janin hingga keluar
Pada kala II ini memiliki ciri khas:
a) His terkoordinir, kuat, cepat. Dan lebih lama kira-kira 2-3
menit sekali
b) Kepala janintelah turun masuk ruang panggul dan secara
reflektoris menimbulkan rasa ingin mengejan
c) Tekanan pada rektu, ibu merasa ingin BAB
d) Anus membuka
Pada waktu his kepala janin mulai kelihatan, vulva membuka dan
perineum meregang, dengan his dan mengejan yang terpimpin
kepala akan lahir dan diikuti seluruh badan janin.
Lama pada kala II pada primi dan multipara berbeda yaitu:
(a) Primipara kala II berlangsung 1,5 jam – 2 jam.
(b) Multipara kala II berlangsung 0,5 jam – 1 jam.
3) Kala III: Kala Uri
Yaitu waktu pelepasan dan pengeluaran uri (plasenta).
Setelah bayi lahir kontraksi rahim berhenti sebentar, uterus teraba
keras dengan fundus uteri setinggi pusat dan berisi plasenta yang
menjadi tebal 2 kali sebelumnya. Beberapa saat kemudian timbul
103
his pengeluaran dan pelepasan uri, dalam waktu1-5 menit plasenta
terlepas terdorong ke dalam vagina dan akan lahir spontan atau
dengan sedikit dorongan (brand brow), seluruh proses biasanya
berlangsung 5-30 menit setelah bayi lahir. Dan pada pengeluaran
plasenta biasanya disertai dengan pengeluaran darah kira-kira
100-200 cc.
4) Kala IV (Tahap Pengawasan)
Tahap ini digunakan melakukan pengawasan terhadap
bahaya perdarahan. Pengawasan ini dilakukan selama kurang
lebih dua jam. Dalam tahap ini ibu masih mengeluarkan darah
dari vagina, tapi tidak banyak, yang berasal dari pembuluh darah
yang ada di dinding rahim tempat terlepasnya plasenta, dan
setelah beberapa hari akan mengeluarkan cairan sedikit darah
yang disebut lochea yang berasal dari sisa-sisa jaringan (Walyani
dan Purwoastuti, 2015).
h. Kebutuhan Dasar Selama Persalinan
Kebutuhan dasar ibu dalam proses persalinan meliputi :
1) Kebutuhan fisiologis
a) Oksigen
b) Makan dan minum
c) Istirahat selama tidak ada his.
d) Kebersihan badan terutama genetalia.
e) Buang air kecil.
f) Pertolongan persalinan yang terstandart.
g) Penjahitan perineum bila perlu.
2) Kebutuhan rasa aman
a) Memilih tempat dan penolong persalinan.
b) Informasi tentang proses persalinan atau tindakan yang akan
dilakukan.
c) Posisi tidur yang dikehendaki ibu.
d) Pendampingan oleh keluarga.
104
e) Pantauan selama persalinan.
f) Intervensi yang diperlukan.
3) Kebutuhan dicintai dan mencintai
a) Pendampingan oleh suami/keluarga.
b) Kontak fisik (memberi sentuhan ringan).
c) Masase untuk mengurangi rasa sakit.
d) Berbicara dengan suara yang lemah, lembut serta sopan.
4) Kebutuhan harga diri
a) Merawat bayi sendiri dan menetekinya.
b) Asuhan kebidanan dengan memperhatikan privacy ibu.
c) Pelayanan yang bersifat empati dan simpati.
d) Informasi bila akan melakukan tindakan.
e) Memberikan pujian pada ibu terhadap tindakan positif yang
ibu lakukan.
5) Kebutuhan aktualisasi diri
a) Memilih tempat dan penolong sesuai keinginan.
b) Memilih pendamping selama persalinan.
c) Bounding and attachment.
d) Ucapan selamat atas kelahiran anaknya (Walyani dan
Purwoastuti, 2015).
i. Tanda dan Gejala Inpartu
1) Tanda persalinan sudah mulai dekat
a) Terjadi lightening
Menjelang minggu ke-36, pada primigravida terjadi penurunan
fundus uteri karena kepala bayi sudah masuk pintu atas
panggul yang disebabkan :
(1) Kontraksi Braxton Hicks
(2) ketegangan perut dinding
(3) Gaya berat janin di mana kepala ke arah bawah
Masuknya kepala bayi ke pintu atas panggul
(1) Terasa ringan di bagian atas, rasa sesaknya berkurang
105
(2) Di bagian bawah terasa sesak
(3) Terjadi kesulitan saat berjalan
(4) Sering miksi (beser kencing)
(b) Terjadinya his permulaan
Makin tua hamil, pengeluaran estrogen dan progesteron makin
berkurang, sehingga oksitosin dapat menimbulkan kontraksi
yang lebih sering, sebagai his palsu.
Sifat his permulaan (palsu) :
(1) Rasa nyeri ringan di bagian bawah
(2) Datangnya tidak teratur
(3) Tidak ada perubahan pada servix atau pembawa tanda
(4) Durasi pendek
(5) Tidak bertambah bila beraktivitas (Walyani dan
Purwoastuti, 2015).
2) Gejala persalinan sebagai berikut:
a) Kekuatan his makin sering terjadi dan teratur dengan jarak
kontraksi yang semakin pendek
b) Dapat terjadi pengeluaran pembawa tanda, yaitu:
a. Pengeluaran lendir
b. Lendir bercampur darah
c) Dapat disertai ketuban pecah dini
d) Pada pemeriksaan dalam, dijumpai perubahan servix:
(1) Perlunakan servix
(2) Perdarahan servix
(3) Terjadi pembukaan servix (Walyani dan Purwoastuti,
2015).
j. Mekanisme Persalinan
1) Penurunan (engagement)
Pada minggu-minggu akhir kehamilan atau pada saat
persalinan dimulai kepala masuk lewat pintu atas panggul (PAP),
umumnya dengan presentasi biparietal atau 70% pada panggul
106
ginekoid. Masuknya kepala pada primi pada bulan terakhir
kehamilan dan pada multi terjadi pada permulaan persalinan.
Masuknya kepala kedalam PAP yaitu diawali dengan fleksi
ringan, sutura sagitalis/SS melintang (bila SS di tengah-tengah
jalan lahir atau disebut sinklitismus, bila SS tidak ditengah-tengah
jalan lahir atau disebut asinklitismus) (Sukarni, 2013).
Tabel 2.6 Penurunan Kepala Janin Menurut Sistem Perlimaan Periksa Luar Periksa Dalam Keterangan
= 5/5
Kepala diatas PAP,
mudah digerakkan.
=4/5
H I-II Sulit digerakkan,
bagian terbesar
kepala belum masuk
panggul.
= 3/5
H II-III Bagian terbesar
kepala belum masuk
panggul.
=2/5
H III+ Bagian terbesar
kepala sudah masuk
panggul.
=1/5
H III-IV Kepala didasar
panggul.
= 0/5
H IV Kepala di perineum.
Sumber : Saifuddin (ed). 2013. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan
Maternal dan Neonatal
2) Descent
Descent terjadi ketika bagian terbawah janin telah melewati
panggul. Descent / penurunan terjadi akibat tiga kekuatan yaitu
tekanan dari cairan amnion, tekanan langsung kontraksi fundus
pada janin dan kontraksi diafragma serta otot – otot abdomen ibu
pada saat persalinan, dengan sumbu jalan lahir yaitu Sinklitismus,
107
Asinklistismus anterior, dan Asinklitismus posterior
(Cunningham dkk, 2013).
3) Fleksi
Fleksi meningkat selama persalinan. Pada umumnya terjadi
fleksi penuh/sempurna sehingga sumbu panjang kepala sejajar
sumbu panggul untuk membantu penurunan kepala selanjutnya.
Fleksi: kepala janin fleksi, dagu menempel ke thoraks, posisi
kepala berubah dari diameter oksipito frontalis (puncak kepala)
menjadi diameter suboksipito-breghmatikus (belakang kepala)
(Margareth ZH, 2013).
4) Rotasi internal (putaran paksi dalam)
Dengan fleksi kepala janin memasuki ruang panggul sampai
didasar panggul, kepala janin berada didalam keadaan fleksi
maksimal. Kepala yang sedang turun menemui diafragma pelvis
yang berjalan dari belakang ke bawah depan. Akibat kombinasi
elastisitas diafragma pelvis dan tekanan intrauteri disebabkan oleh
his yang berulang, kepala menjadi berotasi atau disebut juga
dengan putar paksi dalam (Prawirohardjo, 2014).
5) Ekstensi
Ubun-ubun kecil akan berotasi kearah depan, sehingga di
dasar panggul ubun-ubun kecil dibawah simfisis, dan dengan
suboksiput sebagai hipomoklion, kepala mengadakan gerakan
defleksi untuk dapat dilahirkan. Pada setiap his vulva lebih
membuka dan kepala makin tampak. Perineum menjadi makin
lebar dan tipis, anus membuka dinding rectum. Dengan kekuatan
his bersama dengan kekuatan mengejan, berturut-turut tampak
bregma, dahi, muka, dan akhirnya dagu (Prawirohardjo, 2014).
6) Rotasi eksternal (putaran paksi luar)
Sesudah kepala lahir, kepala segera mengadakan rotasi yang
disebut putar paksi luar. Putaran paksi luar adalah gerakan
kembalinya ke posisi sebelumputar paksi dalam terjadi, untuk
108
menyesuaikan diri dengan kedudukan kepala dengan punggung
anak (Prawirohardjo, 2014).
7) Ekspulsi
Bahu melintasi pintu atas rongga panggul dalam keadaan
miring. Didalam rongga panggul bahu akan menyesuaikan diri
dengan bentuk panggul yang dilaluinya, sehingga di dasar
panggul. Apabila kepala sudah lahir, bahuu akan berada dalam
posisi depan belakanh. Selanjutnya dilahirkan bahu depan terlebih
dahulu, baru kemudian bahu belakang. Demikian pula dilahirkan
trokater depan terlebih dahulu baru kemudian trokater belakang
(Prawirohardjo, 2014).
Gambar 2.3 Mekanisme Persalinan Normal Sumber : Manuaba dkk, 2013, Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan KB untuk
Pendidikan Bidan, Jakarta
Keterangan : Mekanisme persalinan dan posisi ubun-ubun kecil kiri
depan (LOA).
a) Penurunan (engagement)
b) Descent
c) Fleksi
d) Putar paksi dalam
e) Ekstensi
f) Putar paksi luar (restitusi)
g) Ekspulsi
109
k. Tanda Bahaya Persalinan
1) Tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg dengan sedikitnya satu
tanda lain atau gejala preeklamsi
2) Temperatur lebih dari 38oC, Nadi lebih dari 100 x/menit dan DJJ
kurang dari 120 x/menit atau lebih dari 160 x/menit
3) Kontraksi kurang dari 3 kali dalam 10 menit, berlangsung kurang
dari 40 detik, lemah saat di palpasi
4) Patograf melewati garis waspada pada fase aktif.
5) Cairan amniotic bercampur mekonium, darah dan bau (Walyani
dan Purwoastuti, 2015).
l. Penapisan Ibu Bersalin Normal
Apabila didapati salah satu atau lebih penyulit maka pasien harus
dirujuk.
Tabel 2.7 Penapisan Ibu Bersalin No Jenis Penapisan Ya Tidak
1 Riwayat bedah besar
2 Pendarahan pervaginam
3 Persalinan kurang bulan usia kehamilan kurang dari 37
minggu
4 Ketuban pecah disertai mekonium yang kental
5 Ketuban pecah lama
6 Ketuban pecah pada persalinan kurang bulan (usia
kehamilan kurang dari 37 minggu)
7 Ikterus
8 Anemia berat
9 Tanda gejala infeksi
10 Pre-eklamsi /hipertensi dalam kehamilan
11 Tinggi fundus 40cm /lebih
12 Gawat janin
13 Primipara dalam fase aktif kala satu persalinan dan
kepala janin masih5/5
14 Presentasi bukan belakang kepala
15 Prentasi ganda /majemuk
16 Kehamilan ganda atau gamelli
17 Tali pusat menumbung
18 Syok
19 Suami TKI
20 Suami pelayaran
21 Suami /bumil bertato
22 HIV/AIDS
23 PMS
24 Anak mahal
Sumber : JNPK-KR, 2017
110
m. Lima Benang Merah Persalinan
Ada lima aspek dasar atau Lima Benang Merah, yang penting dan
saling terkait dalam asuhan persalinan yang bersih dan aman. Berbagai
aspek tersebut melekat pada setiap persalinan, baik normal maupun
patologis. Lima Benang Merah tersebut adalah :
1) Membuat Keputusan Klinik
Membuat keputusan merupakan proses yang menentukan
untuk menyelesaikan masalah dan menentukan asuhan yang
diperlukan oleh pasien. Keputusan itu harus akurat, komprehensif
dan aman, baik bagi pasien dankeluarganya maupun petugas yang
memberikan pertolongan. Tujuan langkah dalam membuat
keputusan klinik :
a) Pengumpulan data utama dan relevan untuyk membuat
keputusan
b) Menginterpretasikan data dan mengidentifikasi masalah
c) Membuat diagnosa atau menentukan masalah yang terjadi
dihadapi
d) Menilai adanya kebutuhan dan kesiapan
2) Asuhan sayang ibu
Asuhan sayang ibu adalah aasuhan yang menghargai budaya,
kepercayaan dan keinginan sang ibu.
a) Panggil ibu sesuai dengan namanya, hargai dan perlakaukan
ibu sesuai martabatnya
b) Jelaskan semua asuhan dan perawatan kepada ibu sebelum
memulai asuhan
c) Jelaskan proses persalinan
d) Anjurkan ibu untuk bertanya
e) Dengarkan dan tanggapi pertanyaan ibu
f) Berikan dukungan pada ibu
g) Anjurkan ibu untuk ditemani suami/keluarga
h) Ajarkan keluarga cara memperhatikan dan mendukung ibu
111
i) Lakukan praktek pencegahan infeksi yang baik
j) Hargai privasi ibu
k) Anjurkan ibu memilih posisi persalinan
l) Anjurkan ibu untuk makan dan minum
m) Hargai praktek tradisional yang tidak merugikan kesehatan ibu
n) Hindari tindakan berlebihan yang membahaykan ibu
o) Anjurkan ibu untuk memeluk bayinya sesegera mungkin
p) Membantu memulai IMD
q) Siapkan rencana rujukan (bila perlu)
r) Mempersiapkan persalinan dengan baik
3) Pencegahan infeksi
Upaya yang dilakukan untuk mencegah atau memutuskan transmisi
mikroorganisme antar individu (dari ibu ke bayi baru lahir atau dari
ibu ke penolong persalinan atau sebaliknya).
a) Cuci tangan
b) Memakai sarung tangan dan perlengkapan pelindung lainnya
c) Menggunakan teknik asepsis atau aseptik
d) Memproses alat bekas pakai
e) Menangani peralatan tajam dengan aman
f) Menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan
4) Pencatatan ( Rekam Medik ) Asuhan Persalinan
Pencatatan (pendokumentasian) adalah bagian penting dari
proses membuat keputusan klinik karena memungkinkan penolong
persalinan untuk terus menerus memperhatikan asuhan yang
diberikan selama proses persalinan dan kelahiran bayi. Partograf
adalah bagian terpenting dari proses pencatatan selama persalinan.
Pencatatan rutin adalah penting karena :
a) Sebagai alat bantu untuk membuat keputusan klinik dan
mengevaluasi kesesuaian dan keefektifan asuhan atau
perawatan, mengidentifikasi kesenjangan pada asuhan yang
112
diberikan dan untuk membuat perubahan dan peningkatan pada
rencana asuhan atau perawatan.
b) Sebagai tolak ukur keberhasilan dalam proses membuat
keputusan klinik.
c) Sebagai catatan permanen tentang asuhan, perawatan dan obat
yang diberikan.
d) Dapat dibagikan di antara para penolong persalinan sehingga
lebih dari satu penolong persalinan akan memberikan perhatian
dan asuhan pada ibu atau bayi baru lahir.
e) Dapat mempermudah kelangsungan asuhan dari satu
kunjungan ke kunjungan berikutnya, dari satu penolong
persalinan ke penolong persalinan lainnya, atau dari seorang
penolong persalinan ke fasilitas kesehatan lainnya.
f) Dapat digunakan untuk penelitian atau studi kasus.
g) Diperlukan untuk memberi masukan data statistik nasional dan
daerah, termasuk catatan kematian dan kesakitan ibu atau bayi
baru lahir.
Aspek – aspek penting dalam pencatatan adalah :
a) Tanggal dan waktu asuhan diberikan
b) Identifikasi penolong persalinan.
c) Paraf atau tanda tangan (dari penolong persalinan) pada semua
catatan.
d) Mencakup informasi yang berkaitan secara tepat, dicatat
dengan jelas dan dapat dibaca.
e) Suatu sistem untuk memelihara catatan pasien sehingga selalu
siap tersedia.
f) Kerahasiaan dokumen – dokumen medis, ibu harus diberikan
salinan catatan (catatan klinik antenatal, dokumen – dokumen
rujukan, dan lain – lain) beserta panduan yang jelas mengenai :
(1) Maksud dari dokumen – dokumen tersebut
(2) Kapan harus dibawa
113
(3) Kepada siapa harus diberikan
(4) Bagaimana menyimpan dan mengamankannya, baik di
rumah atau selama perjalanan ke tempat rujukan.
Beberapa hal yang perlu diingat :
a) Catat semua data, hasil pemeriksaan, diagnosis, obat – obat,
asuhan atau perawatan, dan lain – lain
b) Jika tidak dicatat, maka dapat dianggap bahwa asuhan tersebut
tidak dilakukan.
c) Pastikan setiap partograf bagi setiap pasien diisi dengan
lengkap dan benar.
5) Rujukan
Jika ditemukan suatu masalah dalam persalinan, sering kali
sulit untuk melakukan upaya rujukan dengan cepat, hal ini karena
banyak faktor yang mempengaruhi. Penundaan dalam membuat
keputusan dan pengiriman ibu ke tempat rujukan akan
menyebabkan tertundanya ibu mendapat penatalaksanaan yang
memadai, sehingga dapat menyebabkan tingginya angka kematian
ibu. Rujukan tepat waktu merupakan bagian dari asuhan sayang ibu
dan menunjang terwujudnya program Safe Motherhood . Di bawah
ini merupakan akronim yang dapat di gunakan petugas kesehatan
dalam mengingat hal-hal penting dalam mempersiapkan rujukan
untuk ibu dan bayi :
a) B (Bidan)
Pastikan bahwa ibu dan bayi baru lahir didampingi oleh
penolong persalianan yang kompeten untuk melaksanakan
gawat darurat obstetri dan BBL untuk dibawa ke fasilitas
rujukan.
b) A (Alat)
Bawa perlengkapan dan alat-alat untuk asuhan persalinan,
masa nifas, dan BBL(tambung suntik, selang iv, alat resusitasi,
dan lain-lain) bersama ibu ke tempat rujukan. Perlengkapan
114
dan bahan-bahan tersebut meungkin diperlukan jika ibu
melahirkan dalam perjalanan ke fasilitas rujukan.
c) K (Keluarga)
Beritahu Ibu dan Keluarga mengenai kondisi terakhir ibu
dan bayi dan mengapa ibu dan bayi perlu dirujuk. Jelaskan
pada mereka alasan dan tujuan merujuk ibu ke fasilitas rujukan
tersebut.
d) S (Surat)
Berikan surat keterangan rujukan ke tempat rujukan. Surat
ini memberikan identifikasi mengenai ibu dan BBL cantumkan
alasan rujukan dan uraikan hasil penyakit, asuhan atau obat-
obatan yang diterima ibu dan BBL.
e) O (obat)
Bawa obat-obat esensial pada saat mengantar ibu ke
fasilitas rujukan.
f) K (Kendaraan)
Siapkan kendaraan uyang paling memungkinkan untuk
merujuk ibu dalam kondisi cukup nyaman.
g) U (Uang)
Ingatkan keluarga untuk membawa uang dalam jumlah
yang cukup untuk membeli obat-obatan yang diperlukan dan
bahan-bahan kesehatan lainnya selama ibu dan bayi di fasilitas
rujukan.
h) Da (Darah dan Doa)
Persiapan darah baik dari anggota keluarga maupun
kerabat sebagai persiapan jika terjadi penyulit (JNPK-KR,
2017).
115
n. Partograf
1) Pengertian
Partograf adalah alat bantu untuk memantau kemajuan kala 1
persalinan dan informasi untuk pembuat keputusan klinik (JNPK-
KR, 2017).
Partograf adalah alat bantu yang digunakan selama persalinan
(Prawirohardjo, 2014).
2) Tujuan
a) Mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan dengan
menilai pembukaan serviks melalui pemeriksaan dalam.
b) Mendeteksi apakah proses persalinan bejalan secara normal.
Dengan demikian dapat pula mendeteksi secara dini
kemungkinan terjadinya partus lama (JNPK-KR, 2017).
3) Penggunaan partograf
a) Digunakan untuk semua ibu dalam fase aktif kala I persalinan
dan merupakan elemen penting dari asuhan persalinan.
Partograf harus digunakan untuk semua persalinan, baik
normal maupun patologis. Partograf sangat membantu
penolong persalinan dalam memantau, mengevaluasi dan
membuat keputusan klinik, baik persalinan dengan penyulit
maupun yangtidak disertai dengan penyulit.
b) Selama persalinan dan kelahiran bayi di semua tempat (rumah,
Puskesmas, klinik bidan swasta, rumah sakit, dll).
c) Secara rutin oleh semua penolong persalinan yang memberikan
asuhan persalinan kepada ibu dan proses kelahiran bayinya
(JNPK-KR, 2017).
4) Mencatat temuan pada partograf
a) Informasi Tentang Ibu
Lengkapi bagian awal (atas) partograf secara teliti pada saat
memulai asuhan persalinan. Waktu kedatangan (tertulis
sebagai : “jam atau pukul” pada partograf) dan perhatikan
116
kemungkinan ibu datang pada fase laten. Catat waktu
pecahnya selaput ketuban.
b) Kondisi Janin
Bagan atas grafik pada partograf adalah untuk pencatatan
denyut jantung janin (DJJ), air ketuban dan penyusupan
(kepala janin).
(1) Denyut jantung janin
Nilai dan catat DJJ setiap 30 menit (lebih sering jika
ada tanda-tanda gawat janin). Setiap kotak di bagian atas
partograf menunjukan DJJ. Catat DJJ dengan memberi
tanda titik pada garis yang sesuai dengan angka yang
menunjukan DJJ. Kemudian hubungkan yang satu dengan
titik lainnya dengan garis tegas bersambung. Kisaran
normal DJJ terpapar pada patograf diantara 180 dan 100.
Akan tetapi penolong harus waspada bila DJJ di bawah
120 atau di atas 160.
(2) Warna dan adanya air ketuban
Nilai air kondisi ketuban setiap kali melakukan
pemeriksaan dalam dan nilai warna air ketuban jika
selaput ketuban pecah. Catat semua temuan-temuan dalam
kotak yang sesuai di bawah lajur DJJ. Gunakan lambang-
lambang berikut ini :
U : Selaput ketuban masih utuh (belum pecah)
J : Selaput ketuban sudah pecah dan air ketuban jernih
M : Selaput ketuban sudah pecah dan air ketuban
bercampur meconium
D : Selaput ketuban sudah pecah dan air ketuban
bercampur darah
K : Selaput ketuban sudah pecah tapi air ketuban tidak
mengalir lagi (kering)
117
(3) Penyusupan (Moulase) tulang kepala janin
Penyusupan adalah indikator penting tentang seberapa
jauh kepala bayi dapat menyesuaikan diri terhadap bagian
keras (tulang) panggul ibu. Semakin besar derajat
penyusupannya atau tumpang tindih antara tulang kepala
semakin menunjukan risiko disporposi kepala panggul
(CPD). Ketidak mampuan untuk berakomodasi atau
disporposi ditunjukan melalui derajat penyusupan atau
tumpang tindih (molase) yang berat sehingga tulang
kepala yang saling menyusup, sulit untuk dipisahkan.
Apabila ada dugaan disporposi kepala panggul maka
penting untuk tetap memantau kondisi janin serta
kemajuan persalinan. Setiap kali melakukan pemeriksaan
dalam, nilai penyusupan antar tulang (molase) kepala
janin. Catat temuan yang ada dikotak yang sesuai di
bawah lajur air ketuban. Gunakan lambang-lambang
berikut ini :
0 : Tulang-tulang kepala janin terpisah, sutura dengan
mudah dapat dipalpasi
1 : Tulang-tulang kepala janin hanya saling bersentuhan
2 : Tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih tetapi
masih dapat dipisahkan
3: Tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih dan
tidak dapat dipisahkan (JNPK-KR, 2017).
c) Kemajuan persalinan
Kolom dan lajur kedua pada partograf adalah untuk
pencatatan kemajuan persalinan. Angka 0-10 yang tertera
dikolom paling kiri adalah besarnya dilatasi serviks. Nilai
setiap angka sesuai dengan besarnya dilatasi serviks dalam
satuan sentimeter dan menempati lajur dan kotak tersendiri.
Perubahan nilai atau perpindahan lajur satu ke lajur yang lain
118
menunjukan penambahan dilatasi serviks sebesar 1 cm. Pada
lajur dan kotak yang mencatat penurunan bagian terbawah
janin tercantum angka 1-5 yang sesuai dengan metode
perlimaan. Setiap kotak segi empat atau kubus menunjukan
waktu 30 menit untuk pencatatan waktu pemeriksaan, DJJ,
kontraksi uterus dan frekwensi nadi ibu.
a) Pembukaan servik
Saat ibu berada dalam fase aktif persalinan, catat pada
partograf setiap temuan dari setiap pemeriksaan. Tanda
“X” harus dicantumkan di garis waktu yang sesuai dengan
lajur besarnya pembukaan serviks. Perhatikan :
(1) Pilih angka pada tepi kiri luar kolom pembukaan
serviks yang sesuai dengan besarnya pembukaan
serviks pada fase aktif persalinan yang diperoleh dari
hasil pemeriksaan dalam.
(2) Untuk pemeriksaan pertama pada fase aktif
persalinan, temuan (pembukaan serviks dari hasil
pemeriksaan dalam harus dicantumkan pada garis
waspada. Pilih angka yang sesuai dengan bukaan
serviks (hasil periksa dalam) dan cantumkan tanda
“X” pada ordinat atau titik silang garis dilatasi serviks
dan garis waspada.
(3) Hubungkan tanda “X” dari setiap pemeriksaan dengan
garis utuh (tidak terputus) (JNPK-KR, 2017).
b) Penurunan bagian terbawah janin
Setiap melakukan periksa dalam (4 jam) cantumkan hasil
pemeriksaan penurunan kepala (perlimaan) yang
menunjukkan seberapa jauh bagian terbawah janin telah
memasuki rongga panggul. Pada persalinan normal,
kemajuan pembukaan serviks selalu diikuti dengan
turunnya bagian terbawah janin.
119
Tulisan “turunnya kepala” dan garis tidak terputus dari 0-5
,tertera disisi yang sama dengan angka pembukaan
serviks. Berikan tanda “O” yang ditulis pada garis waktu
yang sesuai. Sebagai contoh, jika hasil pemeriksaan
palpasi kepala diatas simfisis pubis adalah 4/5 maka
tuliskan pada tanda O di garis angka 4. Hubungan tanda O
dari setiap pemeriksaan dengan garis tidak terputus
(JNPK-KR, 2017).
c) Garis waspada dan garis bertindak
Garis waspada dimulai pada pembukaan serviks 4 cm dan
berakhir pada titik dimana pembukaan lengkap diharapkan
terjadi jika laju pembukaan adalah 1 cm per jam.
Pencatatan selama fase aktif persalinan harus dimulai di
garis waspada. Jika pembukaan serviks mengarah ke
sebelah kanan garis waspada (pembukaan kurang dari 1
cm per jam), maka harus dipertimbangkan adanya penyulit
.Garis bertindak tertera sejajar dan di sebelah kanan
(berjarak 4 jam) garis waspada. Jika pembukaan serviks
telah melampaui dan berada di sebelah kanan garis
bertindak maka hal ini menunjukan perlu dilakukan
tindakan untuk menyelesaikan persalinan (JNPK-KR,
2017).
d) Jam dan waktu
Setiap kotak pada partograf untuk kolom waktu (jam)
menyatakan satu jam sejak dimulainya fase aktif
persalinan (JNPK-KR, 2017).
e) Kontraksi uterus
Di bawah lajur waktu partograf, terdapat lima kotak
dengan tulisan “kontraksi per 10 menit” di sebelah luar
kolom paling kiri. Setiap kotak menyatakan satu kontraksi.
Setiap 30 menit, raba dan catat jumlah kontraksi dalam 10
120
menit dan lamanya kontraksi dalam satuan detik.
Nyatakan jumlah kontraksi yang terjadi dalam waktu 10
menit dengan cara mengisi kotak kontraksi yang tersedia
dan disesuaikan dengan angka yang mencerminkan
temuan dari hasil pemeriksaan kontraksi. Sebagai contoh
jika ibu mengalami 3 kontraksi dalam waktu satu kali 10
menit, maka lakukan pengisian pada 3 kotak kontraksi
(JNPK-KR, 2017).
f) Obat-obatan dan cairan yang diberikan
(1) Oksitosin, jika tetesan (drip) oksitosin sudah dimulai,
dokumentasikan setiap 30 menit jumlah unit oksitosin
yang diberikan per volume cairan IV dan dalam tetes
per menit.
(2) Obat-obatan lain, catat semua pemberian obat-obatan
tambahan dan/atau cairan I.V dalam kotak yang sesuai
dengan kolom waktunya (JNPK-KR, 2017).
g) Kondisi ibu
Bagian terbawah lajur dan kolom pada halaman depan
partograf, terdapat kotak atau ruang untuk mencatat
kondisi kesehatan dan kenyamanan ibu selama persalinan
(1) Nadi, tekanan darah dan suhu tubuh
Angka disebelah kiribagian partograf ini berkaitan
dengan nadi dan tekanan darah ibu
(a) Nilai dan catat nadi ibu setiap 30 menit selama
fase aktif persalinan (lebih sering jika diduga
adanya penyulit). Beri tanda titik (·) pada kolom
waktu yang sesuai.
(b) Nilai dan catat tekanan darah ibu setiap 4 jam
selama fase aktif persalinan (lebih sering jika
diduga adanya penyulit). Beri tanda panah pada
partograf pada kolom waktu yang sesuai:↕
121
(c) Nilai dan catat temperatur tubuh ibu (lebih sering
jika terjadi peningkatan mendadak atau diduga
adanya infeksi) setiap 2 jam dan catat temperatur
tubuh pada kotak yang sesuai.
(2) Volume urin, protein dan aseton
Ukur dan catat jumlah produksi urin ibu sedikitnya
setiap 2 jam (setiap kali ibu berkemih). Jika
memungkinkan setiap kali ibu berkemih lakukan
pemeriksaan aseton dan proteinuria (JKPK-KR,
2017).
5) Halaman belakang partograf
Halaman belakang partograf merupakan bagian untuk mencatat
hal-hal yang terjadi selama proses persalinan dan kelahiran, serta
tindakan–tindakan yang dilakukan sejak persalinan kala I hingga
IV (termasuk bayi baru lahir). Itulah sebabnya bagian ini disebut
sebagai catatan persalinan. Nilai dan catatkan asuhan yang telah
diberikan pada ibu dalam masa nifas terutama selama persalinan
kala IV untuk memungkinkan penolong persalinan mencegah
terjadinya penyulit dan membuat keputusan klinik, terutama pada
pemantauan kala IV (mencegah terjadinya perdarahan
pascapersalinan). Selain itu, catatan persalinan (yang sudah diisi
dengan lengkap dan tepat) dapat pula digunakan untuk menilai
memantau sejauh mana telah dilakukan pelaksanaan asuhan
persalinan yang bersih dan aman (JNPK-KR, 2017). Cara
pengisian:
a) Data dasar
Data dasar terdiri dari tanggal, nama bidan, tempat persalinan,
alamat tempat persalinan, catatan, alasan merujuk, tempat
rujukan dan pendamping pada saat merujuk. Isi data pada
masing-masing tempat yang telah disediakan, atau dengan cara
memberi tanda pada kotak di samping jawaban yang sesuai.
122
b) Kala I
Kala I terdiri dari pertanyaan-pertanyaan tentang temuan
selama fase laten, grrafik melewati atau tidak, masalah-
masalahn lain yang timbul, penatalaksanaannya, dan hasil
penatalaksanaan tersebut.
c) Kala II
Kala II terdiri dari episiotomi, pendamping persalinan, gawat
janin, distosia bahu, masalah lain, penatalaksanaan masalah
tersebut dan hasilnya
d) Kala III
Kala III terdiri dari lama kala III, pemberian oksitosin,
penegangan tali pusat terkendali, rangsangan pada fundus,
plasenta lahir lengkap, plasenta tidak lahir > 30 menit, laserasi,
atonia uteri, jumlah perdarahan, masalah penyerta,
penatalaksanaan dan hasilnya, isi jawaban pada tempat yang
disediakan dan beri tanda pada kotak di samping jawaban yang
sesuai (JNPK-KR, 2017).
Untuk derajat laserasi diklasifikasikan berdasarkan luasnya
robekan:
Gambar 2.4 Derajat Laserasi Perineum
Sumber : JNPK-KR, 2017. Asuhan Persalinan Normal. Halaman 108
Keterangan :
(1) Derajat Satu : Mukosa Vagina, Komisura Posterior, dan
kulit Perineum.
(2) Derajat Dua : Mukosa vagina, komisura posterior, kulit
perineum, dan otot perineum.
123
(3) Derajat Tiga : Mukosa vagina, komisura posterior, kulit
perineum, otot perineum, dan otot sfingter ani.
(4) Derajat Empat : Mukosa vagina, komisura posterior, kulit
perineum , otot perineum, otot sfingter ani, dan dinding
depan rektum.
e) Bayi baru lahir
Informasi tentang bayi baru lahir terdiri dari berat dan panjang
badan, jenis kelamin, penilaian kondisi bayi baru lahir,
pemberian ASI, masalah penyerta, penatalaksanaan terpilih
dan hasilnya. Isi jawaban pada tempat yang disediakan serta
beri tanda ada kotak di samping jawaban yang sesuai (JNPK-
KR, 2017).
f) Kala IV
(1) Kala IV berisis data tentang tekanan darah, nadi,
temperatur, TFU, kontraksi, kandung kemih dan
perdarahan.
(2) Pemantauan pada kala IV ini sangat penting, terutama
untuk menilai resiko atau keispan penolong
mengantisispasi komplikasi perdarahan pascapersalinan.
(3) Pemanatauan kala IV dilakukan setiap 15 menit sekali
dalam 1 jam pertama setelah melahirkan selanjutnya setiap
30 menit pada satu jam berikutnya.
(4) Pantau temperature tubuh setiap jam dalam dua jam
pertama pasca persalinan
(5) Isikan hasil pemeriksaan pada kolom yang sesuai.
(6) Bila timbul masalah pada kala IV, tuliskan jenis dan cara
penanganannya pada bagian masalah kala IV dan bagian
berikutnya.
(7) Bagian yang diarsir tidak perlu diisi
(8) Catatkan semua temuan selama kala IV persalinan (JNPK-
KR, 2017).
126
2. Konsep Dasar Asuhan Kebidanan Persalinan Normal
a. Pengkajian Data
1) Data Subyektif
Data subyektif dikumpulkan melalui anamnesis.Tujuan
anamnesis adalah mengumpulkan informasi tentang riwayat
kesehatan, kehamilan dan persalinan (JNPK-KR, 2017).
a) Identitas
(1) Nama
Mengetahui nama klien dan suami berguna untuk
memperlancar komunikasi dalam asuhan sehingga tidak
terlihat kaku dan lebih akrab (Walyani, 2015).
(2) Usia
Umur perlu diketahui guna mengetahui apakah klien
dalam kehamilan yang beresiko atau tidak.Usia di
bawah 16 tahun dan di atas 35 tahun merupakan umur-
umur yang beresiko tinggi untuk hamil. Umur yang
baik untuk kehamilan maupun persalinan adalah 19-25
tahun (Walyani, 2015).
(3) Agama
Tanyakan pilihan agama klien dan berbagai praktik
terkait agama yang harus diobservasi.Informasi ini
dapat menuntun ke suatu diskusi tentang pentingnya
agama dalam kehidupan klien, tradisi keagamaan dalam
kehamilan dan kelahiran, perasaan tentang jenis
kelamin tenaga kesehatan, dan pada beberapa kasus,
penggunaan produk darah (Walyani, 2015).
(4) Pendidikan
Tanyakan pendidikan tertinggi yang klien tamatkan
juga minat, hobi, dan tuuan jangka panjang.Informasi
ini membantu klinis memahami klien sebagai individu
127
dan memberi gambaran kemampuan baca-
tulisnya.(Walyani, 2015).
(5) Pekerjaan
Mengetahui pekerjaan klien adalah penting untuk
mengetahui apakah klien berada dalam keadaan utuh
dan untuk mengkaji potensi kelahiran, prematur dan
pajanan terhadap bahaya lingkungan kerja, yang dapat
merusak janin (Walyani, 2015).
(6) Alamat
Alamat rumah klien perlu diketahui bidan untuk lebih
memudahkan saat pertolongan persalinan dan untuk
mengetahui jarak rumah dengan tempat rujukan
(Walyani, 2015).
b) Keluhan utama
Keluhan utama adalah alasan kenapa klien datang ke tempat
bidan.Hal ini disebut tanda atau gejala.Dituliskan sesuai
dengan yang diungkapkan oleh klien serta tanyakan juga
sejak kapan hal tersebut dikeluhkan oleh klien. Menurut
(Manuaba, 2013), tanda-tanda persalinan adalah:
(1) Terjadinya his persalinan. His persalinan mempunyai
ciri khas pinggang terasa nyeri yang menjalar ke depan,
sifatnya teratur, interval makin pendek, dan
kekuatannya makin besar, mempunyai pengaruh
terhadap pembukaan serviks, makin beraktivitas (jalan)
makin bertambah.
(2) Pengeluaran lendir dan darah (pembawa tanda).
Dengan his persalinan terjadi perubahan pada serviks
yang menimbulkan pendataran dan pembukaan.
Pembukaan menyebabkan lendir yang terdapat pada
kanalis servikalis lepas. Terjadi perdarahan karena
kapiler pembuluh darah pecah.
128
(3) Pengeluaran cairan. Pada beberapa kasus terjadi
ketuban pecah yang menimbulkan pengeluaran cairan.
Sebagian besar ketuban baru pecah menjelang
pembukaan lengkap. Dengan pecahnya ketuban
diharapkan persalinan berlangsung dalam waktu 24
jam.
(4) Gejala utama pada kala II menurut (Manuaba, 2013),
adalah:
(a) His semakin kuat, dengan interval 2 sampai 3 menit,
dengan durasi 50 sampai 100 detik.
(b) Menjelang akhir kala I, ketuban pecah dan ditandai
dengan pengeluaran cairan secara mendadak.
(c) Ketuban pecah pada pembukaan mendekati lengkap
diikuti keinginan mengejan, karena tertekannya
pleksus Frankenhauser.
c) Riwayat kesehatan
Kondisi medis tertentu berpotensi mempengaruhi ibu atau
bayi atau keduanya.Calon ibu mengetahui bahwa
penyakitnya dapat memperburuk atau berpeluang
menyebabkan bayi sakit atau meninggal. Menanyakan
Riwayat Kesehatan, yang meliputi:
(1) Riwayat kesehatan ibu
(a) Penyakit yang pernah diderita
(b) Penyakit yang sedang diderita
(c) Apakah pernah dirawat
(d) Berapa lama dirawat
(e) Dengan penyakit apa dirawat
(2) Riwayat kesehatan keluarga
(a) Penyakit menular
(b) Penyakit keturunan/genetikRiwayat kebidanan
129
d) Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu
Menanyakan Riwayat Kehamilan Lalu, yang meliputi:
(1) Jumlah kehamilan (Graviid/G)
(2) Jumlah anak yang hidup (L)
(3) Jumlah kelahiran prematur (P)
(4) Jumlah keguguran (A)
(5) Persalinan dengan tindakan (operasi sesar, vakum,
forsep)
(6) Riwayat perdarahan pada persalinan atau pasca
persalinan
(7) Kehamilan dengan tekanan darah tinggi
(8) Berat bayi < 2,5 atau 4 kg
(9) Masalah lain
Setiap komplikasi yang terkait dengan kehamilan harus
diketahui sehingga dapat dilakukan antisipasi terhadap
komplikasi berulang. Sebagai contoh, kehamilan
ektopik cenderung berulang
e) Riwayat kehamilan sekarang
Menanyakan Riwayat Kehamilan Sekarang, yang meliputi:
(1) HPHT (Hari Pertama Haid Terakhir)
(2) TP (Taksiran Persalinan)/Perkiraan Kelahiran
(3) kehamilan yang ke-
(4) Masalah-masalah
(a) TM I : tanyakan pada klien apakah klien ada
masalah seperti : hiperemesis gravidarum, anemia,
dan lain-lain.
(b) TM II : tanyakan pada klien apa yang pernah ia
rasakan pada trimester II kehamilan pada
kehamilan sebelumnya.
130
(c) TM III : tanyakan pada klien apa yang pernah ia
rasakan pada trimester III kehamilan pada
kehamilan sebelumnya.
(d) ANC (Antenatal Care/Asuhan Kehamilan)
(e) Tempat ANC
(f) Penggunaan obat-obatan
(g) Imunisasi : TT (Tetanus Toxoid)
(h) Penyuluhan yang didapat
f) Status pernikahan
(1) Menikah
(2) Usia saat menikah
(3) Lama pernikahan
(4) Dengan suami sekarang
(5) Isteri keberapa dengan suami sekarang
g) Riwayat KB
(1) Metode
(2) Lama
(3) Masalah
h) Kebiasaan hidup sehat
(1) Pola Nutrisi
(a) Jenis makanan
(b) Porsi
(c) Frekuensi
(d) Pantangan
(e) Alasan pantang
(2) Personal Hygiene
(a) Frekwensi mandi
(b) Frekwensi gosok gigi
(c) Frekwensi ganti pakaian
(d) Kebersihan vulva
(3) Pola aktifitas
131
(4) Pola eliminasi
(a) BAB (Buang Air Besar)
1) Frekwensi
2) Warna
3) Masalah
(2) BAK (Buang Air Kecil)
1) Frekwensi
2) Warna
3) Bau
4) Masalah
2) Data Obyektif
Data obyektif adalah informasi yang dikumpulkan berdasarkan
pemeriksaan/pengamatan terhadap ibu atau bayi baru lahir
(Walyani, 2015).
a) Pemeriksaan Umum
(1) Kesadaran dan Keadaan umum
Compos mentis (kesadaran baik), gangguan kesadaran
(apatis, samnolen, spoor, koma) (Walyani, 2015).
(2) Tanda-tanda vital
(a) Tekanan darah
Tekanan darah yang normal adalah 110/180 mmHg
sampai 140/190 mmHg, hati-hati adanya hipertensi
atau preeklamsi (Walyani, 2015).
(b) Nadi
Nadi normal adalahm 60 sampai 100 menit.Bila
abnormal mungkin ada kelainan paru-paru atau
jantung (Walyani, 2015).
(c) Suhu
Suhu badan normal adalah 36,50C sampai
37,50C.Bila suhu lebih tinggi dari 37,5
0C
kemungkinan ada infeksi (Walyani, 2015).
132
(d) Pernapasan
Sedikit peningkatan frekuensi pernapasan masih
normal selama persalinan, dan mencerminkan
peningkatan metabolisme yang terjadi (Walyani,
2015).
b) Pemeriksaan fisik
(1) Inspeksi
(a) Muka
Periksa palpebra, konjungtiva, dan sklera. Periksa
palpebra untuk memeriksa oedema umum. Periksa
konjungtiva dan sclera untuk memperkirakan
adanya anemia dan ikterus.
(b) Dada
Bila tampak sesak, kemungkinan ada kelainan
jantung yang dapat meningkatkan terjadinya resiko
yang lebih tinggi baik bagi ibu maupun bayinya.
(c) Payudara
Inspeksi bentuk payudara, benjolan, pigmentasi
putting susu. Palpasi adanya benjolan (tumor
mamae) dan colostrums.
(d) Abdomen
Inspeksi pembesaran perut (bila pembesaran perut
itu berlebihan kemungkinan asites, tumor, ileus,
dan lain-lain), pigmentasi di linea alba, nampakkah
gerakan anak atau kontraksi rahim, adakah strie
gravidarum atau luka bekas operasi.
(e) Tangan dan tungkai
Inspeksi pada tibia dan jari untuk melihat adanya
oedema dan varices.Bila terjadi oedema pada
tempat-tempat tersebut kemungkinan terjadinya
pre-eklamsia.
133
(f) Vulva
Inspeksi untuk mengetahui adanya oedema, varices,
keputihan, perdarahan, luka, ciran yang keluar, dan
sebagainya.
(2) Palpasi
(a) Abdomen
Pada ibu bersalin perlu dilakukan pemeriksaan
TFU, yaitu pada saat tidak sedang kontraksi
dengan menggunakan pita ukur.Kontraksi uterus
perlu dipantau mengenai jumlah kontraksi selama
10 menit, dan lama kontraksi.Pemeriksaan DJJ
dilakukan selama atau sebelum puncak kontraksi
pada lebih dari satu kontraksi.Presentasi janin, dan
penurunan bagian terendah janin juga perlu
dilakukan pemeriksaan.Sebelum melakukan
pemeriksaan abdomen, anjurkan ibu untuk
mengosongkan kandung kemih. Kandung kemih
harus sering diperiksa setiap 2 jam untuk
mengetahui adanya distensi juga harus
dikosongkan ntuk mencegah obstruksi persalinan
akibat kandung kemih yang penuh, yang akan
mencegah penurunan bagian presentasi janin dan
trauma pada kandung kemih akibat penekanan
yang lama yang akan menyebabkan hipotonia
kandung kemih dan retensi urine selama periode
pascapartum awal (Walyani, 2015).
(b) Genetalia
Tanda-tanda inpartu pada vagina terdapat
pengeluaran pervaginam berupa blody slym,
tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva
membuka sebagai tanda gejala kala II (Manuaba,
134
2012). Pada genetalia dilakukan pemeriksaan
adanya luka atau massa termasuk kondilomata,
varikositas vulva atau rektum, adanya perdarahan
pervaginam, cairan ketuban dan adanya luka parut
di vagina. Luka parut di vagina mengindikasikan
adanya riwayat robekan perineum atau tindakan
episiotomi sebelumnya (Walyani, 2015).
(c) Anus
Perineum mulai menonjol dan anus mulai
membuka. Tanda ini akan tampak bila betul-betul
kepala sudah di dasar pangul dan mulai membuka
pintu (Walyani, 2015).
(d) Ekstremitas
Terutama pemeriksaan reflek lutut.Reflek lutut
negatif pada hipovitaminose dan penyakit urat
saraf.Edema ekstremitas merupakan tanda klasik
preeklampsia, bidan harus memeriksa dan
mengevaluasi pada pergelangan kaki, area pretibia,
atau jari. Edema pada kaki dan pergelangan kaki
biasanya merupakan edema dependen yang
disebabkan oleh penurunan aliran darah vena
akibat uterus yang membesar (Walyani, 2015)
3) Pemeriksaan Khusus
(a) Palpasi
(1) Leopold I
Tujuannya untuk mengetahui tinggi fundus
uteri dan bagian yang berada di fundus.
(2) Leopold II
Tujuannya yaitu untuk mengetahui batas
kiri/kanan pada uterus ibu, yaitu punggung
atau ekstremitas.
135
(3) Leopold III
Tujuannya untuk mengetahui
presentasi/bagian terbawah janin yang ada di
simfisis ibu.
(4) Leopold IV
Tujuan dari leopold IV yaitu untuk mengetahui
seberapa jauh masuknya bagian terendah janin
ke dalam PAP apakah divergen atau
konvergen.
(b) Pemeriksaan dalam
Yang perlu dilakukan dalam pemeriksaan dalam
adalah
(1) Memeriksa genetalia eksterna, memerhatikan
ada tidaknya luka atau massa (benjolan)
termasuk kodiloma, varikositas vulva atau
rektum, atau luka parut di perineum.
(2) Menilai cairan vagina dan menentukan bercak
darah, perdarahan pervaginam atau mekonium:
(a) Jika ada perdarahan pervaginam dilarang
melakukan pemeriksaan dalam.
(b) Jika ketuban sudah pecah, perhatikan
warna dan bau air ketuban. Melihat
pewarnaan mekonium, kekentalan dan
pemeriksaan DJJ.
(c) Jika mekonium encer dan DJJ normal,
meneruskan memantau DJJ dengan
seksama menurut petunjuk partograf.
(d) Jika mekonium kental, menilai DJJ dan
merujuk.
(e) Jika tercium bau busuk, mungkin telah
terjadi tanda infeksi.
136
(f) Jika ketuban belum pecah jangan
melakukan amniotomi.
(3) Adanya luka parut di vagina mengindikasikan
adanya riwayat robekan perineum atau
tindakan episiotomi sebelumnya. Hal ini
merupakan informasi peting untuk
menentukan tindakan pada saat kelahiran bayi.
(4) Menilai pembukaan dan penipisan serviks.
(5) Memastikan tali pusat dan/ atau bagian-bagian
kecil (tangan atau kaki) tidak teraba pada saat
melakukan periksa dalam.
(6) Menilai penurunan bagian terbawah janin dan
menentukan bagian yang masuk ke dalam
rongga panggul.
(7) Jika bagian terbawah kepala, memastikan
penunjuknya (ubun-ubun kecil, ubun-ubun
besar) dan celah (sutura) sagitalis untuk
menilai derajat penyusupan atau tumpang
tindih tulang kepala serta menilai ukuran
kepala janin dengan ukuran jalan lahir apakah
sesuai.
b. Menyusun diagnosa
Data dasar yang telah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga dapat
merumuskan diagnosa atau masalah yang spesifik. Rumusan
diagnosa dan masalah keduanya digunakan karena masalah tidak
dapat didefinisikan seperti diagnosa tetapi tetap membutuhkan
penanganan. Masalah sering berkaitan dengan hasil pengkajian. Pada
langkah ini bidan mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial
berdasarkan rangkaian masalah atau diagnosa yang sudah
diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila
memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengawasi pasien
137
bidan bersiap-siap bila masalah potensial benar-benar terjadi.
Mengantisipasi perlunya tindakan segera oleh bidan dan/dokter
untuk konsultasi atau ditangani bersama dengan anggota tim
kesehatan lain (Walyani, 2015).
c. Merencanakan Asuhan kebidanan
Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang
sudah teridentifikasi dari kondisi/masalah klien, tapi juga dari
kerangka pedoman antisipasi terhadap klien tersebut, apakah
kebutuhan perlu konseling, penyuluhan dan apakah pasien perlu
dirujuk karena ada masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah
kesehatan lain. Pada langkah ini tugas bidan adalah merumuskan
rencana asuhan sesuai dengan hasil pembahasan rencana bersama
klien dan keluarga, kemudian membuat kesepakatan bersama
sebelum melaksanakannya (Walyani, 2015).
Langkah-langkah APN
Menurut (JNPK-KR,2017) tahapan asuhan persalinan normal terdiri
dari 60 langkah adalah:
I. Mengenali gejala dan tanda kala dua
1. Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala dua.
a. Ibu merasa ada dorongan kuat dan meneran
b. Ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada
rektum dan vagina.
c. Perineum tampak menonjol
d. Vulva-vagina dan sfingter ani membuka
II. Menyiapkan pertolongan persalinan
2. Pastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan
esensial untuk menolong persalinan dan penatalaksanaan
komplikasi ibu dan bayi baru lahir. Untuk bayi asfiksia
persiapkan: tempat datar dan keras, 2 kain dan 1 handuk
bersih dan kering, lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm
dari tubuh bayi
138
a. Menggelar kain di atas perut ibu dan tempat resusitasi
serta ganjal bahu bayi.
b. Menyiapkan oksitosin 10 unit dan alat suntik steril sekali
pakai di dalam partus set.
3. Pakai Celemek Plastik (APD).
4. Melepaskan semua perhiasan yang dipakai di bawah siku.
Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih yg
mengalir dan mengeringkan tangan dengan handuk satu kali
pakai/handuk pribadi yang bersih.
5. Memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi atau steril
untuk semua pemeriksaan dalam.
6. Memasukkan oksitosin ke dalam tabung suntik dengan
memakai sarung tangan DTT atau steril (pastikan tidak
terjadi kontaminasi pada alat suntik).
III. Memastikan pembukaan lengkap & keadaan janin baik.
7. Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan
hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan
kapas atau kasa yang dibasahi air DTT.
a. Jika introitus vagina, perineum atau anus
terkontaminasi tinja, bersihkan dengan seksama dari
arah depan ke belakang
b. Buang kapas atau kasa pembersih (terkontaminasi)
dalam wadah yang tersedia
c. Ganti sarung tangan jika terkontaminasi
(dekontaminasi, lepaskan dan rendam dalam larutan
klorin 0,5% ).
8. Lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa
pembukaan sudah lengkap. Bila selaput ketuban belum
pecah, dan pembukaan sudah lengkap, maka lakukan
amniotomi.
139
9. Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan
tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan
klorin 0,5%, kemudian lepaskan dan rendam dalam keadaan
terbalik di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Cuci
kedua tangan setelah sarung tangan dilepaskan.
10. Periksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi/saat
relaksasi uterus untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas
normal (120-160 x/menit).
a. Mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal.
b. Mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam, DJJ
dan semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya
pada partograf.
IV. Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses
bimbingan meneran
11. Beritahukan pada ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan
keadaan janin baik. serta bantu ibu berada dalam
menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan
keinginannya.
a. Tunggu hingga timbul rasa ingin meneran, lanjutkan
pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu dan janin
(ikuti pedoman penatalaksanaan fase aktif) serta
dokumentasikan semua temuan yang ada.
b. Jelaskan pada anggota keluarga tentang bagaiman
peran mereka untuk mendukung dan memberi
semangat pada ibu untuk meneran secara benar.
12. Minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran.
(Bila ada rasa ingin meneran dan terjadi kontraksi yang
kuat, bantu ibu ke posisi setengah duduk atau posisi lain
yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman).
13. Laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ada
dorongan kuat untuk meneran :
140
a. Bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan
efektif.
b. Dukung dan beri semangat pada saat meneran dan
perbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai.
c. Bantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai
pilihannya (kecuali posisi berbaring terlentang dalam
waktu yang lama).
d. Anjurkan ibu untuk beristirahat diantara kontraksi.
e. Anjurkan keluarga memberi dukungan dan semangat
untuk ibu. Berikan asupan cairan per-oral (minum) yang
cukup.
f. Menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai.
g. Segera rujuk jika bayi belum atau tidak segera lahir
setelah 2 jam meneran pada primigravida atau setelah 1
jam meneran pada multigravida.
14. Anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil
posisi yang nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan
untuk meneran dalam 60 menit.
V. Persiapan pertolongan kelahiran bayi
15. Letakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut
ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter
5-6 cm.
16. Letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian di bawah
bokong ibu.
17. Buka tutup partus set dan perhatikan kembali kelengkapan
alat & bahan.
18. Pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan.
VI. Persiapan pertolongan kelahiran bayi.
19. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm
membuka vulva maka lindungi perineum dengan satu
tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan
141
yang lain menahan kepala bayi untuk menahan posisi
defleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu untuk
meneran perlahan atau bernafas cepat dan dangkal.
20. Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat & ambil
tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi dan segera lanjutkan
proses kelahiran bayi :
a. Jika tali pusat melilit leher secara longgar, lepaskan
lewat bagian atas kepala bayi.
b. Jika tali pusat melilit leher secara kuat, klem tali pusat di
dua tempat, dan potong diantara dua klem tersebut.
21. Setelah kepala lahir, tunggu kepala bayi melakukan paksi
luar secara spontan.
22. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara
biparental, anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi.
Dengan lembut gerakkan kepala ke arah bawah dan distal
hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis dan
kemudian gerakkan arah atas dan distal untuk melahirkan
bahu belakang.
23. Setelah kedua bahu lahir, satu tangan menyangga kepala
dan bahu belakang, tangan yang lain menelusuri lengan, dan
siku anterior bayi serta menjaga bayi terpegang dengan
baik.
24. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas
berlanjut ke punggung, bokong, tungkai dan kaki. Pegang
kedua mata kaki (masukkan telunjuk diantara kaki dan
pegang masing-masing mata kaki dengan ibu jari dan jari-
jari lainnya pada sisi yang lain agar bertemu dengan jari
telunjuk).
VII. Penanganan bayi baru lahir
25. Lakukan penilaian (selintas)
a. Apakah bayi cukup bulan?
142
b. Apakah bayi menangis kuat dan atau bernafas tanpa
kesulitan/ tidak megap-megap ?
c. Apakah bayi bergerak dengan aktif ?
Bila salah satu jawaban “tidak” lanjut ke langkah
resusitasi pada asfiksia bayi baru lahir, bila semua
jawaban “ya” lanjut ke langkah 26.
26. Keringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian
tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan
verniks. Ganti handuk basah dengan handuk atau kain yang
kering. Biarkan bayi di atas perut ibu.
27. Periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi
bayi dalam uterus (hamil tunggal).
28. Beritahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus
berkontraksi baik.
29. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin
10 unit IM (intramuskuler) di 1/3 paha atas bagian distal
lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin).
30. Dalam waktu 2, pegang tali pusat dengan satu tangan pada
sekitar 5 cm dari pusar, kemudian jari telunjuk dan jari
tengah tangan yang lain menjepit tali pusat dan menggeser
hingga 3 cm proksimal dari pusar bayi. Klem tali pusat pada
titik tersebut dan tahan pada posisinya, gunakan jari
telunjuk dan jari tengah tangan lain untuk mendorong tali
pusat kea rah ibu sekitar 5 cm dan klem tali pusat pada
sekitar 2 cm distal dari klem pertama.
31. Pemotongan dan pengikatan tali pusat
a. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah
dijepit (lindungi perut bayi), lakukan pengguntingan tali
pusat di antara 2 klem.
b. Ikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada
satu sisi kemudian melingkarkan kembali benang
143
tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi
lainnya.
c. Lepaskan klem dan masukkan dalam wadah yang
telah disediakan.
32. Letakkan bayi agar ada kontak kulit ibu ke kulit bayi.
Letakkan bayi tengkurap di dada ibu.Luruskan bahu bayi
sehingga bayi menempel di dada/perut ibu.Usahakan kepala
berada diantara payudara ibu dengan posisi lebih rendah
dari puting payudara ibu.
a. Selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan pasang
topi di kepala bayi.
b. Biarkan bayi melakukan kontak kulit selama 1 jam.
c. Bayi akan berhasil menyusu sekitar 30-60 menit dan
menyusu sekitar 10-15 menit pada satu payudara.
d. Biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam
meskipun bayi sudah berhasil menyusu.
Kala III
VIII. Penatalaksanaan aktif persalinan kala tiga
33. Pindahkan klem pada tali pusat sekitar 5-10 cm dari vulva.
34. Letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu, di tepi
atas simfisis untuk mendeteksi, sedangkan tangan lain
menegangkan tali pusat.
35. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah
bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah
belakang atas (dorso-kranial) secara hati-hati (untuk
mencegah inversio uteri). Jika plasenta tidak lahir setelah
30-40 detik, hentikan PTT dan tunggu hingga timbul
kontraksi berikutnyadan ulangi prosedur tersebut. Jika
uterus tidak segera berkontraksi minta ibu, suami atau
anggota keluarga untuk melakukan stimulasi puting susu.
144
36. Bila ada penekanan bagian bawah dinding depan uterus
kearah dorsal ternyata diikuti pergeseran tali pusat kearah
distal maka lanjutkan dorongan kearah cranial hingga
placenta dapat dilahirkan.
a. Ibu boleh meneran tetapi tali pusat hanya ditegangkan
sesuai dengan sumbu jalan lahir.
b. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem
hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva dan lahirkan
plasenta.
c. Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit menegangkan
tali pusat :
1) Berikan dosis ulangan oksitosin 10 unit IM.
2) Lakukan kateterisasi (aseptik) jika kandung kemih
penuh.
3) Minta keluarga untuk menyiapkan rujukan.
4) Ulangi penegangan tali pusat selama 15 menit
berikutnya.
5) Jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit setelah bayi
lahir atau bila terjadi perdarahan, segera lakukan
plasenta manual.
37. Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta
dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga
selaput ketuban terpilin, kemudian lahirkan dan tempatkan
plasenta pada wadah yang telah disediakan. Jika selaput
ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau steril untuk
melakukan eksplorasi sisa selaput kemudian gunakan jari-
jari tangan atau klem DTT untuk mengeluarkan bagian
selaput yang tertinggal.
38. Segera setelah plasenta & selaput ketuban lahir, lakukan
masase uterus, letakkan telapak tangan di fundus dan
lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut
145
hingga uterus berkontraksi (fundus teraba keras). Lakukan
tindakan yang sesuai jika uterus tidak berkontraksi selama
15 detik massage.
IX. Menilai perdarahan
39. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum.
Lakukan penjahitan bila laserasi derajat 1 atau 2 dan atau
menimbulkan perdarahan. Bila ada robekan yang
menimbulkan perdarahan aktif, segera lakukan penjahitan.
40. Periksa kedua sisi plasenta baik bagian ibu maupun bayi
pastikan selaput ketuban lengkap & utuh. Masukkan
plasenta ke dalam kantung plastik atau tempat khusus.
Kala IV
41. Melakukan asuhan pasca persalinan
42. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi
perdarahan per vaginam.
43. Pastikan kandung kemih kosong, jika penuh lakukan
kateterisasi.
44. Celupkan tangan yang masih menggunakan sarung tangan
kedalam larutan chlorine 0,5%, lepas secara terbalik dan
rendam sarung tangan dalam larutan chlorine 0,5% selama
10 menit. Cuci tangan dan keringkan menggunakan handuk
bersih.
45. Ajarkan ibu dan keluarga cara melakukan massage uterus
dan menilai kontraksi..
46. Memeriksa nadi ibu dan pastikan keadaan umum ibu baik.
47. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah.
48. Pantau tanda-tanda bahaya pada bayi setiap 15 menit.
Pastikan bayi bernafas normal 40-60 kali/menit.
a. Jika bayi sulit bernafas, merintih, atau retraksi dinding
dada bawah yang berat lakukan resusitasi dan segera
rujuk ke RS.
146
b. Jika bayi bernafas terlalu cepat atau sesak nafas, segera
rujuk ke RS.
c. Jika kaki teraba dingin, pastikan ruangan hangat.
Lakukan kembali kontak kulit ibu dan bayi dan selimuti
bersama dengan ibunya.
49. Bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Bersihkan sisa
cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai
pakaian yang bersih dan kering.
50. Pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI.
Anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dan
makanan yang diinginkannya.
51. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan
klorin 0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas
peralatan setelah didekontaminasi.
52. Buang bahan-bahan yg terkontaminasi ke tempat sampah
yang sesuai.
53. Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%.
54. Celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%,
balikkan bagian dalam ke luar dan rendam dalam larutan
klorin 0,5% selama 10 menit. Cuci kedua tangan dengan
sabun dan air mengalir.
55. Pakai sarung tangan bersih /DTT untuk vitamin K1 1 mg di
paha kiri bawah lateral dan salep mata/tetes mata profilaksis
infeksi setelah 1 jam kelahiran.
56. Lakukan pemeriksaan fisik lanjutan (setelah 1 jam kelahiran
bayi). Pastikan kondisi bayi tetap baik.(pernafasan bayi
normal 40-60 x/menit, suhu tubuh 36,50C-37,5
0C) setiap 15
menit.
57. Setelah 1 jam dari pemberian vitamin K1 berikan suntikan
imunisasi hepatitis B dipaha kanan bawah lateral. Letakkan
bayi dijangkauan ibu agar sewaktu-waktu dapat disusukan.
147
58. Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik kedalam
larutan chlorine 0,5% dan rendam selama 10 menit.
59. Cuci tangan dan keringkan menggunakan handuk bersih dan
kering.
60. Lengkapi partograf (halaman depan dan belakang).
d. Melaksanakan asuhan kebidanan
Pada langkah ini rencana asuhan yang komperhensif yng telah
dibuat dapat dilaksanakan secara efisien seluruhnya oleh bidan atau
dokter atau tim kesehatan lain (Walyani, 2015).
e. Evaluasi
Melakukan evaluasi hasil dari asuhan yang telah diberikan meliputi
pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah
terpenuhi sesuai dengan diagnosa/masalah (Walyani, 2015).
f. Dokumentasian SOAP
Model dokumentasi yang digunakan dalam asuhan kebidanan yaitu
dalam bentuk catatan perkembangan karena bentuk asuhan yang
diberikan berkesinambungan dan menggunakan proses yang terus
menerus dengan menggunakan subjektif, objektif, analisis, dan
penatalaksanaan (SOAP) yang merupakan salah satu metode
pendokumentasian.
1) S = Subjektif
Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data
klien melalui anamnesis antara lain tanggal, tahun, waktu,
biodata, riwayat, termasuk kondisi klien. Catatan data spesifik
atau fokus.Tanda dan gejala subjektif yang didapatkan dari
hasil bertanya pada klien, suami dan keluarga.Catatan ini
berhubungan dengan masalah sudut pandang klien.Ekspresi
klien mengenai kekhawatiran dan keluhannya dicatat sebagai
kutipan langsung atau ringkasan yang berhubungan dengan
diagnosa.
148
2) O = Objektif
Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data
klien melalui pengamatan dan terukur, pemeriksaan fisik klien
didapatkan melalui inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi,
termasuk data penunjang.Data ini memberikan bukti gejala
klinis klien dan fakta yang berhubungan dengan diagnosa.
3) A = Analisis
Menggambarkan pendokumentasian hasil analisis, diagnosis,
dan masalah kebidanan.
4) P = Penatalaksanaan
Mencatat seluruh perencanaan dan penatalaksanaan yang telah
dilakukan, misalnya tindakan antisipatif, tindakan segera,
tindakan secara komprehensif, penyuluhan, dukungan,
kolaborasi, evaluasi/follow up dan rujukan. Dokumentasi
menunjukkan perencanaan yang tepat (Astuti dkk, 2017).
C. Nifas
1. Konsep Dasar Masa Nifas
a. Pengertian
Masa nifas adalah masa dimulai beberapa jam sesudah lahirnya
plasenta sampai 6 minggu setelah melahirkan (Nugroho dkk, 2014).
Masa nifas dimulai setelah kelahira plasenta dan berakhir ketika alat-
alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil yang
berlangsung kira-kira 6 minggu (Nugroho dkk, 2014).
Masa nifas (puerperium) adalah masa pulih kembali, mulai dari
persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti pra-
hamil (Suprijati, 2014).
Masa nifas atau puerperium dimulai sejak 1 jam setelah lahirnya
plasenta sampai dengan 6 minggu (42 hari) setelah itu
(Prawirohardjo, 2014).
149
b. Tahapan Masa Nifas
Menurut Nugroho dkk (2014) tahapan nifas dibagi menjadi :
1) Puerperium dini
Suatu masakepulihan dimana ibu diperbolehkan untuk berdiri dn
berjalan-jalan.
2) Puerperium intermedial
Suatu masa dimana kepulihan dari organ-organ reproduksi
selama kurang lebih 6 minggu.
3) Remote Puerperium
Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam
keadaan sempurna terutamabila ibu selama hamil atau saat
persalinan mengalami komplikasi.
c. Perubahan Fisiologis Masa Nifas
1) Perubahan sistem reproduksi
a) Involusi uterus
Involusi uterus atau pengerutan uterus merupakan suatu
proses dimana uterus kembali ke kondisi sebelum hamil.
Proses involusi uterus adalah sebagai berikut:
(1) Iskemia Miometrium. Hal ini disebabkan oleh kontraksi
dan retraksi yang terus menerus dari uterus setelah
pengeluaran plasenta sehingga membuat uterus menjadi
relatif anemi dan menyebabkan serat otot atrofi.
(2) Atrofi jaringan. Atrofi jaringan terjadi sebagai reaksi
penghentian hormon esterogen saat pelepasan plasenta.
(3) Autolysis. Merupakan proses penghancuran diri sendiri
yang terjadi didalam otot uterus.enzim proteolitik akan
memendekkan jaringan otot yang telah mengendur
hingga panjangnya 10 kali panjang sebelum hamil dan
lebarnya 5 kali lebar sebelum hamil yang terjadi selama
kehamila. Hal ini disebabkan karena penurunan hormon
estrogen dan progesteron.
150
(4) Efek oksitosin. Oksitosin menyebabkan terjadinya
kontraksi dan retraksi otot uterus sehingga akan
menekan pembuluh darah yang mengakibatkan
berkurangnya suplai darah ke uterus. Proses ini
membantu untuk mengurangi situs atau tempat
implantasi plasenta serta mengurangi perdarahan
(Nugroho dkk, 2014).
Tabel 2.8 Ukuran Uterus Setelah Persalinan No Waktu
Involusi
Tinggi Fundus Uteri Berat
Uterus
1. Bayi lahir Setinggi pusat 1000 gram
2. Kala Uri /
Plasenta lahir
2 jari bawah pusat 750 gram
3. 1 minggu Pertengahan pusat-
simpisis
500 gram
4. 2 minggu Tidak teraba di atas
simpisis
350 gram
5. 4-6 minggu Fundus uteri
mengecil (tak teraba)
50 gram
Sumber: Suprijati, 2014, Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas.
HMP Press, Ponorogo, halaman:14-15
b) Involusi Tempat Plasenta
Uterus pada bekas implantasi plasenta merupakan luka yang
kasar dan menonjol ke dalam kavum uteri. Segera setelah
plasenta lahir, dengan cepat luka mengecil, pada akhir
minggu ke-2 hanya sebesar 3-4 cm dan pada akhir nifas 1-2
cm (Nugroho dkk, 2014).
c) Perubahan Ligamen
Setelah bayi lahir, ligamen dan diafragma pelvis fasia yang
meregang sewaktu kehamilan dan saat melahirkan, kembali
seperti sedia kala. Perubahan ligamen yang dapat terjadi
pasca melahirkan antara lain: ligamentum rotundum
menjadi kendor yang mengakibatkan letak uterus menjadi
retrofleksi; ligamen, fasia, jaringan penunjang alat genetalia
menjadi agak kendor (Nugroho dkk, 2014).
151
d) Perubahan pada Serviks
Segera setelah melahirkan, serviks menjadi lembek, kendor,
terkulai dan berbentuk seperti corong. Hal ini disebabkan
korpus uteri berkontraksi, sedangkan serviks tidak
berkonraksi, sehingga perbatasan antara korpus dan serviks
uteri berbentuk cincin. Warna serviks merah kehitam-
hitaman karena penuh pembuluh darah. Namun ostium
eksternum tidak akan kembali sama seperti sebelum hamil,
pada umunya ostium uteri eksternum lebih besar, tetap ada
retak-retak dan robekan-robekan pada pinggirnya (Nugroho
dkk, 2014).
e) Lokia
Lokia adalah eksresi cairan rahim selama masa nifas dan
mempunyai reaksi basa/ Kebidanan alkalis yang membuat
organisme berkembang lebih cepat dari pada kondisi asam
yang ada pada vagina normal (Nugroho dkk, 2014).
Lokia mempunyai bau yang amis (anyir) meskipun tidak
terllau menyengat dan volumenya berbeda-beda pada setiap
wanita.pengeluaran lokia dibagi menjadi lokia rubra,
sanguilenta, serosa dan alba. Total jumlah rata-rata
pengeluaran lokia sekitar 240 hingga 270 ml. (Nugroho
dkk, 2014).
152
Tabel 2.9 Lokia Lokia Waktu Warna Ciri-ciri
Rubra 1-3 hari Merah kehitaman Terdiri dari sel desidua,
verniks, rambut lanugo, sisa
mekonium dan sisa darah
Sanguinolenta 3-7 hari Putih bercampur merah Sisa darah bersampur lendir
Serosa 7-14 hari Kekuningan/kecoklatan Lebih sedikit darah dan lebih
banyak serum, juga terdiri
dari leukosit dan robekan
laserasi plasenta
Alba >14 hari Putih Mengandung leukosit, selaput
lendir serviks dan serabut
jaringan yang mati
Sumber: Nugroho dkk, 2014. Buku Ajar Asuhan Nifas (askeb 3), Bagian Perubahan Fisiologi
Masa Nifas, Yogyakarta, halaman 98.
f) Perubahan pada vulva, vagina dan perineum
Selama proses persalinan vulva dan vagina mengalami
penekanan serta peregangan, setelah beberapa hari
persalinan kedua organ ini kembali dlaam keadaan kendor.
Rugae timbul kembali pada minggu ke tiga. Himen tampak
sebagai tonjolan kecil dan dalam proses pembentukan
berubah menjadi karankulae mitiformis yang khas bagi
wanita multipara. Ukuran vagina akan selalu lebih besar
dibandingkan keadaan saat sebelum persalinan pertama.
Perubahan pada perineum pasca melahirkan terjadi pada
saat perineum mengalami robekan (Nugroho dkk, 2014).
2) Perubahan sistem pencernaan
Selama kehamilan dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya
tingginya kadar progesteron yang dapat mengganggu
keseimbangan cairan tubuh, meningkatkan kolestrol darah, dan
melambatkan kontraksi otot-otot polos. Pasca melahirkan, kadar
progesteron juga mulai menurun. Namun, faal usus memerlukan
waktu 3-4 hari untuk kembali normal.
Beberapa hal yang berkaitan dengan perubahan pada sistem
pencernaan antara lain :
153
a) Nafsu makan
Pemulihan nafsu makan diperlukan waktu 3-4 hari sebelum
faal usus kembali normal. Meskipun kadar progesteron
menurun setelah melahirkan, asupan makanan juga
mengalami penurunan selama 1 atau 2 hari.
b) Motilitas
Penurunan tonus dan motilitas otot traktus cerna menetap
selama waktu yang singkat setelah bayi lahir. Kelebihan
analgesia dan anastesia bisa memperlambat pengembalian
tonus dan motilitas ke keadaan normal.
c) Pengosongan usus
Pasca melahirkan ibu sering mengalami kontipasi. Hal ini
disebabkan tonus otot usus menurun selama proses
persalinan dan awal masa pascapartum, diare sebelum
persalinan, enema sebelum melahirkan, kurang makan,
dehidrasi, hemoroid ataupun laserasi jalan lahir. Sistem
pencernaan pada masa nifas membutuhkan waktu untuk
kembali normal. Beberapa cara agar ibu dapat buang air
besar kembali teratur, antara lain:
(1) Pemberian diet/makanan yang mengandung serat
(2) Pemberian cairan yang cukup
(3) Pengetahuan tentang pola eliminasi pasca melahirkan
(4) Pengetahuan tentang perawatan luka jalan lahir
(5) Bila usaha diatas tidak berhasil dapat dilakukan
pemberian huknah atau obat yang lain (Nugroho dkk,
2014).
3) Perubahan sistem perkemihan
Pada masa hamil, perubahan hormonal yaitu steroid tinggi yang
berperan meningkatkan fungsi ginjal. Begitu sebaliknya, pada
pasca melahirkan kadar steroid menurun sehingga menyebabkan
penurunan fungsi ginjal. Fungsi ginjal kembali normal dalam
154
waktu 1 bulan setelah wanita melahirkan. Urin dalam jumlah
yang besar akan dihasilkan dalam waktu 12-36 jam sesudah
melahirkan (Nugroho dkk, 2014).
4) Perubahan sistem muskuloskeletal/diastasis rectie abdominis
Perubahan sistem muskleton terjadi pada saat umur kehamilan
semakin bertambah. Adaptasi muskuloskelatal ini mencakup
peningkatan berat badan, bergesernya pusat akibat posisi rahim,
relaksasi dan mobilitas. Namun, pada saat postpartum sistem
muskuloskeletal akan berangsur-angsur pulih kembali.
Ambulasi dini dilakukan segera setelah melahirkan, untuk
membantu mencegah komplikasi dan mempercepat involusi
uteri (Nugroho dkk, 2014).
5) Perubahan sistem endokrin
Selama proses kehamilan dan persalinan terdapat perubahan
pada sistem endokrin. Hormon-hormon yang berperan pada
proses tersebut, antara lain:
a) Hormon Plasenta
Pengeluaran plasenta menyebabkan penurunan hormon
yang diproduksi oleh plasenta. Hormon plasenta menurun
dengan cepat pasca persalinan. Penurunan hormon plasenta
(human placental lactogen) menyebabkan kadar gula darah
menurun pada masa nifas. Human Chorioinic Gonadotropin
(HCG) menurun dengan cepat dan menetap selama sampai
10% dalam 3 jam hingga hari ke-7 postpartum dan sebagai
onset pemenuhan mamae pada hari ke-3 postpartum.
b) Hormon pituitary
Hormon pituitary antara lain hormon prolaktin, FSH dan
LH. Hormon prolaktin darah meningkat dengan cepat, pada
wanita tidak menyusui menurun dalam waktu 2 minggu.
Hormon prolakrin berperan dalam pembesaran payudara
untuk merangsang produksi susu. FSH dan LH meningkat
155
pada fase konsentrasi folikuler pada minggu ke-3, dan LH
tetap rendah hingga ovulasi terjadi.
c) Hipotalamik pituitary ovarium
Hipotalamik pituitary ovarium akan mempengaruhi
lamanya mendapatkan menstruasi pada wanita yang
menyusui maupun yang tidak menyusui. Pada wnaita
menyusui mendapatkan menstruasi pada 6 minggu pasca
melahirkan berkisar 16% dan wanita 45% setelah 12
minggu pasca melahirkan. Sedangkan pada wanita yang
tidak menyusui, akan mendapatkan mentruasi berkisar 40%
setelah 6 minggu pasca melahirkan dan 90% setelah 24
minggu.
d) Hormon oksitosin
Hormon oksitosin disekresikan dari kelenjar otak bagian
belakang, bekerja terhadap otot uterus dan jaringan
payudara. Selama tahap ketiga persalinan, hormon oksitosin
berperan dalam pelepasan plasenta dan mempertahankan
kontraksi, sehingga mencegah perdarahan. Isapan bayi
dapat merangsang produksi ASI dan sekresi oksitosin,
sehingga dapat membantu involusi uteri.
e) Hormon esterogen dan progesteron
Volume darah normal selama kehamilan, akan meningkat.
Hormon estrogen yang tinggi memperbesar hormon anti
diuretik yang dapat meningkatkan volume darah.
Sedangkan homron progesteron mempengaruhi otot halus
yang mengurangi perangsangan dan peningkatan pembuluh
darah. Hal ini mempengaruhi saluran kemih, ginjal, usus,
dinding vena, dasar panggul, perineum dan vulva serta
vagina ( Suprijati, 2014).
156
6) Perubahan tanda-tanda vital
a) Suhu badan
Pasca melahirkan suhu badan dapat naik kurang lebih 0,5
derajat Celcius dari keadaan normal. Kenaikan suhu badan
ini akibat dari kerja keras sewaktu melahirkan, kehilangan
cairan maupun kelelahan. Kurang lebih pada hari ke-4
postpartum, suhu badan akan naik lagi. Hal ini diakibatkan
ada pembentukan ASI, kemungkinan payudara
membengkak, maupun kemungkinan infeksi pada
endometrium, mastitis, traktus genetalis ataupun sistem lain.
Apabila kenaikan suhu diatas 38 derajat Celcius, waspada
terhadap infeksi postpartum.
b) Nadi
Denyut nadi normal pada orang dewasa 60-80 kali per
menit. Pasca melahirkan, denyut nadi dapat menjadi
brakikardi maupun lebih cepat. Denyut nadi yang melebihi
100 kali per menit, harus waspada kemungkinan infeksi
atau perdarahan postpartum.
c) Tekanan darah
Tekanan darah adalah tekanan yang dialami pada pembuluh
arteri ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota
tubuh. Tekanan darah normal manusia adalah sistolik 90-
120 mmHg dan diastolik 60-80 mmHg. Pasca melahirkan
pada kasus normal, tekanan darah biasanya tidak berubah.
Perubahan tekanan darah menjadi lebih rendah pasca
melahirkan dapat diakibatkan oleh perdarahan. Sedangkan
tekanan darah tinggi pada post partum merupakan tanda
terjadinya pre eklamsia post partum.
d) Pernafasan
Frekuensi pernafasan normal pada orang dewasa adalah 16-
24 kali per menit. Pada ibu postpartum umumnya
157
pernafasan lambat atau normal. Hal ini dikarenakan ibu
dalam keadaan pemulihan atau dalam kondisi istirahat.
Keadaan pernafasan selalu berhubungan dengan keadaan
suhu dan nadi. Bila suhu nadi tidak normal, pernafasan juga
akan mengikutinya, kecuali apabila ada gangguan khusus
pada saluran nafas. Bila pernafasan pada masa postpartum
menjadi lebih cepat, kemungkinan ada tanda-tanda syok
(Nugroho dkk, 2014).
7) Perubahan sistem kardiovaskuler
Selama kehamilan volume darah normal digunakan untuk
menampung aliran darah yang meningkat, yang diperlukan oleh
plasenta dan pembuluh darah uterin. Penarikan kembali
estregon menyebabkan diuresis terjadi yang secara cepat,
sehingga mengurangi volume plasma kembai pada proporsi
normal. Aliran ini terjadi dalam 2-4 jam pertama setelah
kelahiran bayi. Selama masa nifas ini ibu mengeluarkan banyak
sekali jumlah urine. Hilangnya progesteron membantu
mengurangi retensi cairan yang melekat dengan meningkatnya
volume pada jaringan tersebut selama kehamilan. Pada
persalinan pervaginam kehilangan darah sekitar (200-500 cc).
Bila kelahiran melalui seksio cesaria, maka kehilangan darah
dapat dua kali lipat. Perubahan terdiir dari volunme darah (blood
volume) dan hemotokrit (hoemoconcentration). Bila peralinan
pervaginam, hemotrokit akan naik dan pada seksio cesaria,
hemotrokit cenderung stabil dan kembali normal setelah 4-6
minggu (Suprijati, 2014).
8) Sistem Hematologi
Pada minggu-minggu terakhir kehamilan, kadar fibrinogen
dan plasma serta faktor-faktor pembekuan darah meningkat.
Pada hari pertama postpartum, kadar fibrinogen dan plasma
akan sedikit menurun tetapi darah lebih mengental dengan
158
peningkatan viskositas sehingga meningkatkan faktor
pembekuan darah.
Leukositosis adalah meningkatnya jumlah sel-sel darah
putih sebanyak 15.000 selama persalinan. Jumlah leukosit akan
tetap tinggi selama beberapa hari pertama masa postpartum.
Jumlah sel darah putih akan tetap bisa naik lagi sampai 25.000
hingga 30.000 tanpa adanya kondisi patologis jika wanita
tersebut mengalami persalinan lama.
Penurunan volume dan peningkatan sel darah pada
kehamilan diasosiasikan dengan peningkatan hematokrit dan
hemoglobin pada hari ke 3-7 post partum dan akan normal
dalam 4-5 minggu postpartum. Jumlah kehilangan darah selama
masa persalinan kurang lebih 200-500 ml, minggu pertama
postpartum berkisar 500-800 ml dan selama sisa masa nifas
berkisar 500 ml (Nugroho dkk, 2014).
d. Perubahan Psikologis Masa Nifas
Proses adaptasi psikologis sudah terjadi selama kehamilan,
menjelang proses kelahiran maupun setelah persalinan. Pada periode
tersebut. kecemasan seorang wanita dapat bertambah. Pengalaman
yang unik dialami oleh ibu setelah persalinan. Masa nifas merupakan
masa yang rentan dan terbuka untuk bimbingan dan pembelajaran.
Perubahan peran seorang ibu memerlukan adaptasi. Tanggung jawab
ibu mulai bertambah (Nugroho dkk, 2014).
Fase-fase yang akan dialami oleh ibu pada masa nifas antara
lain:
1) Fase Taking ln
Fase ini merupakan periode ketergantungan, yang
berlangsung dari hari pertama sampai hari ke dua setelah
melahirkan. Ibu terfokus pada dirinya sendiri, sehingga
cenderung pasif terhadap lingkungannya. Ketidaknyamanan
yang dialami antara lain rasa mules. nyeri pada luka jahitan,
159
kurang tidur. kelelahan. Hal yang perlu diperhatikan pada fase
ini adalah istirahat cukup, komunikasi yang baik dan asupan
nutrisi.
Gangguan psikologis yang dapat dialami oleh ibu pada fase
ini adalah:
a) Kekecewaan pada bayinya
b) Ketidaknyamanan sebagai akibat perubahan fisik yang
dialami
c) Rasa bersalah karena belum bisa menyusui bayinya
d) Kritikan suami atau keluarga tentang perawatan
bayinya
2) Fase Taking Hold
Fase ini berlangsung antara 3-10 hari setelah
melahirkan. Ibu merasa khawatir akan ketidakmampuan dan
rasa tanggung jawab dalam perawatan bayinya. Perasaan
ibu lebih sensitif sehingga mudah tersinggung. Hal yang
perlu diperhatikan adalah komunikasi yang baik. dukungan
dan pemberian penyuluhan/pendidikan kesehatan tentang
perawatan diri dan bayinya. Tugas bidan antara Jain:
mengajarkan cara perawatan bayi, cara menyusui yang
benar, cara perawatan luka jahitan, senam nifas, pendidikan
kesehatan gizi, istirahat, kebersihan diri dan lain-Iain.
3) Fase Letting Go
Fase ini merupakan fase menerima tanggungjawab akan
peran barunya. Fase ini berlangsung 10 hari setelah
melahirkan. Ibu sudah mulai dapat menyesuaikan diri
dengan ketergantungan bayinya. Terjadi peningkatan akan
perawatan diri dan bayinya. Ibu merasa percaya diri akan
peran barunya, lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan
dirinya dan bayinya. Dukungan suami dan keluarga dapat
membantu merawat bayi. Kebutuhan akan istirahat masih
160
dipertukan ibu untuk menjaga kondisi fisiknya (Nugroho
dkk, 2014).
e. Kebutuhan Dasar Masa Nifas
1) Nutrisi dan cairan
lbu nifas memerlukan nutrisi dan cairan untuk pemulihan
kondisi kesehatan setelah melahirkan, cadangan tenaga serta
untuk memenuhi produksi air susu. Ibu nifas dianjurkan untuk
memenuhi kebutuhan akan gizi sebagai berikut:
a) Mengkonsumsi makanan tambahan. kurang lebih 500
kalori tiap hari
b) Makan dengan diet gizi seimbang untuk memenuhi
kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan
mineral
c) Minum sedikitnya 3 liter setiap hari
d) Mengkonsumsi tablet besi selama 40 hari post partum
e) Mengkonsumsi vitamin A 200.000 intra unit
Zat-zat yang dibutuhkan ibu pasca persalinan antara lain:
a) Kalori
Kebutuhan kalori pada masa menyusui sekitar 400-500
kalori. Wanita dewasa memerlukan 1800 kalori per
hari. Sebaiknya ibu nifas jangan mengurangi kebutuhan
kalori, karena akan mengganggu proses metabolisme
tubuh dan menyebabkan ASI rusak.
b) Protein
Kebutuhan protein yang dibutuhkan adalah 3 porsi per
hari. Satu protein setara dengan tiga gelas susu, dua
butir telur, lima putih telur, 120 gram keju, 1 ¾ gelas
yoghurt, 120-140 gram ikan/daging/unggas, 200-240
gram 1 tahu atau 5-6 sendok selai kacang.
c) Kalsium dan vitamin D
161
Kalsium dan vitamin D berguna untuk pembentukan
tulang dan gigi. Kebutuhan kalsium dan vitamin D
didapat dari minum susu rendah kalori atau berjemur di
pagi hari. Konsumsi kalsium pada masa menyusui
meningkat menjadi 5 porsi per hari. Satu setara dengan
50-60 gram keju, satu cangkir susu krim, 160 gram ikan
salmon, 120 gram ikan sarden, atau 280 gram tahu
kalsium.
d) Magnesium
Magnesium dibutuhkan sel tubuh untuk membantu
gerak otot. fungsi syaraf dan memperkuat tulang.
Kebutuhan magnesium didapat pada gandum dan
kacang-kacangan.
e) Sayuran hijau dan buah
Kebutuhan yang diperlukan sedikitnya tiga porsi sehari.
Satu porsi setara dengan ⅛ semangka, ¼ mangga, ¾
cangkir brokoli, ½ wortel, ¼ - ½ cangkir sayuran hijau
yang telah dimasak, satu tomat.
f) Karbohidrat kompleks
Selama menyusui, kebutuhan karbohidrat kompleks
diperlukan 6 porsi per hari. Satu porsi setara dengan ½
cangkir nasi, ¼ cangkir jagung pipil, 1 porsi sereal atau
oat, 1 iris roti dari bijian utuh, ½ kue muffin dari bijian
utuh, 2-6 biskuit kering atau crackers, ½ cangkir
kacang-kacangan, ⅔ cangkir kacang koro, atau 40 gram
mi/pasta dari bijian utuh.
g) Lemak
Rata-rata kebutuhan lemak dewasa adalah 4½ porsi
lemak (14 gram perporsi) perharinya. Satu porsi lemak
sama dengan 80 gram keju, 3 sendok makan kacang
tanah atau kenari, 4 sendok makan krim 1 cangkir es
162
krim, ½ buah alpukat, 2 sendok makan selai kacang,
120-140 gram daging tanpa lemak, 9 kentang goreng, 2
iris cake, 1 sendok makan mayones atau mentega, atau
2 sendok makan saus salad.
h) Garam
Selama periode nifas, hindari konsumsi garam
berlebihan. Hindari makanan asin seperti kacang asin,
keripik kentang atau acar.
i) Cairan
Konsumsi cairan sebanyak 8 gelas per hari. Minum
sedikitnya 3 liter tiap hari. Kebutuhan akan cairan
diperoleh dari air putih, sari buah. susu dan sup.
j) Vitamin
Kebutuhan vitamin selama menyusui sangat
dibutuhkan. Vitamin yang diperlukan antara lain:
(1) Vitamin A yang berguna bagi kesehatan kulit,
kelenjar serta mata. Vitamin A terdapat dalam
telur, hati dan keju. Jumlah yang dibutuhkan
adalah 1,300 mcg.
(2) Vitamin B6 membantu penyerapan protein dan
meningkatkan fungsi syaraf. Asupan vitamin B6
sebanyak 2,0 mg per hari. Vitamin B6 dapat
ditemui di daging, hati, padi-padian, kacang polong
dan kentang.
(3) Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan.
meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh.
Terdapat dalam makanan berserat. kacang-
kacanga, minyak nabati dan gandum.
k) Zinc (Seng)
Berfungsi untuk kekebalan tubuh, penyembuhan luka
dan pertumbuhan. Kebutuhan Zinc didapat dalam
163
daging, telur dan gandum. Enzim dalam pencernaan
dan metabolisme memerlukan seng. Kebutuhan seng
setiap hari sekitar 12 mg. Sumber seng terdapat pada
seafood, hati dan daging.
l) DHA
DHA penting untuk perkembangan daya lihat dan
mental bayi. Asupan DHA berpengaruh langsung pada
kandungan dalam ASI. Sumber DHA ada pada telur,
otak, hati dan ikan (Nugroho dkk, 2014).
Tabel 2.10 Perbandingan angka kecukupan energi dan zat gizi wanita
dewasa dan tambahannya untuk ibu hamil dan menyusui
No Zat Gizi Wanita
Dewasa
Ibu
Hamil
Ibu Menyusui
0-6 bulan 7-12
bulan
1 Energi(kkal) 2200 285 700 500
2 Protein(g) 48 12 16 12
3 Vitamin A (Re) 500 200 350 300
4 Vitamin D (mg) 5 5 5 5
5 Vitamin E (mg) 8 2 4 2
6 Vitamin K (mg) 6,5 6,5 6,5 6,5
7 Tiamin (mg) 1,0 0,2 0,3 0,3
8 Riboflavin (mg) 1,2 0,2 0,4 0,3
9 Niasin (mg) 9 0,1 3 3
10 Vitamin B12 (mg) 1,0 0,3 0,3 0,3
11 Asam Folat (mg) 150 150 50 40
12 Piidoksin (mg) 1,6 0,6 0,5 0,5
13 Vitamin C (mg) 60 10 25 10
14 Kalsium (mg) 500 400 400 400
15 Fosfor (mg) 450 200 300 200
16 Besi (mg) 26 20 2 2
17 Seng (mg) 15 5 10 10
18 Yodium (mg) 150 25 50 50
19 Selenium (mg) 55 15 25 20
Sumber: Nugroho dkk, 2014, Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas (Askeb 3), Bagian
Kebutuhan Dasar Ibu Nifas, Yogyakarta, Halaman 138.
2) Ambulasi
Sebagian besar pasien dapat melakukan ambulasi segera
setelah persalinan usai. Aktivitas tersebut amat berguna bagi
semua sistem tubuh, terutama fungsi usus, kandung kemih,
sirkulasi dan paru-paru. Hal tersebut juga membantu mencegah
thrombosis pada pembuluh tungkai dan membantu kemajuan ibu
164
dari ketergantungan peran sakit menjadi sehat. Aktivitas dapat
dilakukan secara bertahap, memberikan jarak antara aktivitas
dan istirahat. Dalam 2 jam setelah bersalin ibu harus sudah bisa
melakukan mobilisasi. Dilakukan secara perlahan-lahan dan
bertahap. Dapat dilakukan dengan miring kanan atau kiri
terlebih dahulu, kemudian duduk dan berangsur-angsur untuk
berdiri dan jalan (Walyani, 2015b).
Keuntungan ambulasi dini adalah:
a) lbu merasa lebih sehat dan kuat
b) Fungsi usus, sirkulasi, paru-paru dan perkemihan lebih baik
c) Memungkinkan untuk mengajarkan perawatan bayi pada
ibu
d) Mencegah trombosis pada pembuluh tungkai
e) Sesuai dengan keadaan Indonesia (sosial ekonomis)
Menurut penelitian mobilisasi dini tidak berpengaruh buruk.
tidak menyebabkan perdarahan abnormal, tidak mempengaruhi
penyembuhan luka episiotomi maupun luka di perut, serta tidak
memperbesar kemungkinan prolapsus uteri. Early ambulation
tidak dianjurkan pada ibu post partum dengan penyulit, seperti
anemia, penyakit jantung, penyakit paru-paru, demam, dan
sebagainya (Nugroho dkk, 2014).
3) Eliminasi : BAB/BAK
Buang air sendiri sebaiknya dilakukan secepatnya. Miksi
normal bila dapat BAK spontan setiap 3-4 jam. Kesulitan BAK
dapat disebabkan karena springter uretra tertekan oleh kepala
janin dan spasme oleh iritasi muskulo spingter ani selama
persalinan. atau dikarenakan oedem kandung kemih selama
persalinan. Lakukan kateterisasi apabila kandung kemih penuh
dan sulit berkemih.
Ibu diharapkan dapat BAB sekitar 3-4 hari post partum.
Apabila mengalami kesulitan BAB/obstipasi. lakukan diet
165
teratur, cukup cairan, konsumsi makanan berserat, olahraga,
berikan obat rangsangan per oral/per rektal atau lakukan klisma
bilamana perlu (Nugroho dkk, 2014).
4) Kebersihan diri dan perineum
Kebersihan diri berguna untuk mengurangi infeksi dan
men'ngkatkan perasaan nyaman. Kebersihan diri meliputi
kebersihan tubuh, pakaian. tempat tidur maupun lingkungan.
Beberapa hal yang dapat dilakukan ibu post partum dalam
menjaga kebersihan diri adalah sebagai berikut:
a) Mandi teratur minimal 2 kali sehari
b) Mengganti pakaian dan alas tempat tidur
c) Menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal
d) Melakukan perawatan perineum
e) Mengganti pembalut minimal 2 kali sehari
f) Mencuci tangan setiap membersihkan daerah genetalia
(Nugroho dkk, 2014).
5) Istirahat
Ibu nifas memerlukan istirahat yang cukup. istirahat tidur
yang dibutuhkan ibu nifas sekitar 8 jam pada malam hari dan 1
jam pada siang hari. Hal-hal yang dapat di|akukan ibu dalam
memenuhi kebutuhan istirahatnya antara lain:
a) Anjurkan ibu untuk cukup istirahat
b) Sarankan ibu untuk melakukan kegiatan rumah tangga
secara perlahan
c) Tidur siang atau istirahat saat bayi tidur
Kurang istirahat dapat menyebabkan:
a) Jumlah ASI berkurang
b) Memperlambat proses involusio uteri
c) Menyebabkan depresi dan ketidakmampuan dalam merawat
bayi sendiri (Nugroho dkk, 2014).
166
6) Seksual
Hubungan seksual dilakukan begitu darah berhenti. Namun
demikian hubungan seksual dilakukan tergantung suami istri
tersebut. Selama periode nifas, hubungan seksual juga dapat
berkurang. Hal yang dapat menyebabkan pola seksual selama
nifas berkurang antara lain:
a) Gangguan/ketidaknyamanan fisik
b) Kelelahan
c) Ketidakseimbangan hormon
d) Kecemasan berlebihan
Pada saat melakukan hubungan seksual sebaiknya
perhatikan waktu, penggunaan kontrasepsi, dispareuni.
kenikmatan dan kepuasan pasangan suami istri (Nugroho dkk,
2014).
7) Latihan/senam nifas
Organ-organ tubuh wanita akan kembali seperti semula
sekitar 6 minggu. Oleh karena itu, ibu akan berusaha
memulihkan dan mengencangkan bentuk tubuhnya. Hal tersebut
dapat dilakukan dengan cara latihan senam nifas. Senam nifas
adalah senam yang dilakukan seiak hari pertama melahirkan
sampai dengan hari ke sepuluh. Beberapa faktor yang
menentukan kesiapan ibu untuk memulai senam nifas antara
lain:
a) Tingkat kebugaran tubuh ibu
b) Riwayat persalinan
c) Kemudahan bayi dalam pemberian asuhan
d) Kesulitan adaptasi post partum
Tujuan senam nifas adalah sebagai berikut:
a) Membantu mempercepat pemulihan kondisi ibu
b) Mempercepat proses involusio uteri
167
c) Membantu memulihkan dan mengencangkan otot panggul,
perut dan perineum
d) Memperlancar pengeluaran lochea
e) Membantu mengurangi rasa sakit
f) Merelaksasikan otot-otot yang menunjang proses kehamilan
dan persalinan
g) Mengurangi kelainan dan komplikasi masa nifas
Manfaat senam nifas antara lain:
a) Membantu memperbaiki sirkulasi darah
b) Memperbaiki sikap tubuh dan punggung pasca persalinan
c) Memperbaiki otot tonus, pelvis dan peregangan otot
abdomen
d) Memperbaiki dan memperkuat otot panggul
e) Membantu ibu lebih relaks dan segar pasca melahirkan
Senam nifas dilakukan pada saat ibu benar-benar pulih dan
tidak ada komplikasi atau penyulit masa nifas atau diantara
waktu makan. Sebelum melakukan senam nifas, persiapan yang
dapat dilakukan adalah:
a) Mengenakan baju yang nyaman untuk olahraga
b) Minum banyak air putih
c) Dapat dilakukan di tempat tidur
d) Dapat diiringi musik
e) Perhatikan keadaan ibu (Nugroho dkk, 2014).
f. Menyusui dan Laktasi
1) Pengertian
Menyusui adalah keterampilan yang dipelajari ibu dan
bayi, dimana keduanya membutuhkan waktu dan kesabaran
untuk pemenuhan nutrisi dan bayi selama 6 bulan. Sedangkan
laktasi adalah keseluruhan proses menyusui mulai dari ASI
diproduksi sampai proses bayi menghisap dan menelan ASI
(Mulyani, 2013).
168
2) Anatomi Payudara
Payudara (mammae, susu) adalah kelenjar yang terletak di
bawah kulit, di atas otot dada. Fungsi dari payudara adalah
memproduksi susu untuk nutrisi bayi. Manusia mempunyai
sepasang kelenjar payudara, yang beratnya lebih 200 gram, saat
hamil 600 gram dan saat menyusui 800 gram.
Payudara disebut glandulla mammae, berkembang sejak
usia janin 6 minggu dan membesar karena pengaruh hormon ibu
yang tinggi yaitu estrogen dan progesterone. Estrogen
meningkatkan pertumbuhan duktus-duktus dan saluran
penampungan.Progesterone merangsang pertumbuhan tunas-
tunas alveoli. Hormon-hormon ini seperti prolactin, growth
hormone, adenoskotikosteroid, dan tiroid juga diperlukan dalam
kelenjar air susu.
Payudara tersusun dari jaringan kelenjar, jaringan ikat, dan
jaringan lemak. Diameter payudara sekitar 10-12 cm. Pada
wanita yang tidak hamil berat rata-rata sekitar 200 gram,
tergantung individu.
Pada akhir kehamilan beratnya berkisar 400-600 gram,
sedangkan pada waktu menyusui beratnya mencapai 600-800
gram.Payudara terbagi menjadi 3 bagian :
a) Korpus (badan), yaitu bagian yang membesar
(1) Korpus alveolus, yaitu terkecil yang memproduksi
susu. Bagian dai alveolus adalah adalah sel aciner,
jaringan lemak, sel plasma, sel otot polos dan pembuluh
darah
(2) Lonulus, yaitu kumpulan dari alveolus
(3) Lobus, yaitu beberapa lobules yang berkumpul menjadi
15-20 lobus pada tiap payudara. ASI disalurkan dari
alveolus ke dalam saluran kecil (duktus), kemudian
169
beberapa duktus bergabung membentuk saluran yang
lebih besar (duktus laktiferus)
b) Areola, yaitu bagian yang kehitaman ditengah
Sinus laktiferus, yaitu saluran dibawah areola yang besar
melebar, akhirnya memusat ke dalam putting dan bermuara
ke luar.Di dalam dinding alveolus maupun saluran-saluran
terdapat otot polos yang bila berkontraksi dapat memompa
ASI keluar.
c) Papilla atau putting, yaitu bagian yang menonjol di puncak
payudara
Papilla atau putting, bagian yang menonjol yang
dimasukkan ke mulut bayi untuk aliran air susu.
Struktur payudara terdiri dari 3 bagian yaitu :
a) Kulit
b) Bagian subkutan (jaringan di bawah kulit)
c) Corpus mammae terdiri dari :
(1) Parenkin : duktus laktiferus, duktulus (duktuli), lobus,
alveoli.
(2) Stroma
Ada 15-20 duktus laktiferus.Tiap duktus bercabang-
cabang menjadi 20-40 duktuli.Duktulus bercabang
menjadi 10-100 alveolus yang berfungsi satu kesatuan
kelenjar.
Masing-masing duktus akan membentuk lobus dan
duktulus akan membentuk lobulus.Duktulus dan
duktus berpusat ke putting sususebelum bermuara ke
putting susu, masing-masing duktus melebar
bermuara pada ampulla atau sinus yang akan
berfungsi sebagai gudang air susu ibu.
Putting susu dan areola (daerah sekitar putting susu
yang berpigmentasi lebih) adalah gudang susu yang
170
mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan
menyusui. Pada umumnya menonjol keluar.
Meskipun demikian, kadang dijumpai putting yang
panjang, datar(flat nipples), atau masuk ke dalam
(inverted nipples). Pada ujung puting susu terdapat
15-52 muara lobus (duktus laktiverus), sedangkan
areola mengandung sejumlah kelenjar, misalnya
kelenjar Montgomery yang berfungsi sebagai kelenjar
minyak yang mengeluarkan cairan agar puting tetap
lunak dan lentur (Suprijati, 2014).
3) Fisiologi Payudara
Selama kehamilan, hormon prolactin dan plasenta meningkat
tetapi ASI biasanya belum keluar karena masih dihambat oleh
kadar estrogen yang tinggi. Pada hari kedua atau ketiga
persalinan, kadar estrogen dan progesterone akan turun drastis,
sehingga pengaruh prolactin lebih dominan dan pada saat inilah
terjadi sekresi ASI. Dengan menyusukan lebih dini terjadi
perangsangan putting susu, terbukalah prolactin hipofisis,
sehingga sekresi ASI semakin lancar.
a) Reflex prolactin
Sewaktu bayi menyusu, ujung saraf yang terdapat pada
putting susu terangsang. Ransangan tersebut oleh serabut
afferent dibawa ke hipotalamus di dasar otak, lalu memacu
hipofise anterior untuk mengeluarkan hormon prolactin ke
dalam darah.Melalui siklus prolactin memacu sel kelenjar
(alveoli) untuk memproduksi ASI. Jumlah prolactin yang
disekresikan dan jumlah susu yang diproduksi berkaitan
dengan stimulasi isapan, yaitu frekuensi, intensitas dan
lamanya bayi menghisap.
b) Reflek aliran (let down reflex)
171
Rangsangan yang ditimbulkan oleh bayi saat menyusui
selain mempengaruhi hipofise anterior juga mempengaruhi
hipofise posterior mengeluarkan hormon oksitosin. Dimana
setelah oksitosin dilepaskan kedalam darah mengacu otot-
otot polos yang mengelilingi alveoli dan duktulus
berkontraksi sehingga memeras air susu dari alveoli,
duktulus, dan sinus menuju putting susu (Suprijati, 2014).
4) Hormon-hormon yang berperan dalam proses laktasi
a) Progesteron, berfungsi mempengaruhi pertumbuhan dan
ukuran alveoli
b) Estrogen, berfungsi menstimulasi sistem saluran ASI agar
membesar sehingga dapat menampung ASI lebih banyak.
Kadar estrogen menurun saat melahirkan dan tetap rendah
untuk beberapa bulan selama tetap menyusui. Sebaliknya,
ibu menyusui menghindari KB hormonal berbasis hormon
estrogen, karena dapat mengurangi jumlah produksi ASI.
c) Follicle Stimulating Hormone (FSH)
d) Luteinizing Hormone (LH)
e) Prolaktin, berperan dalam membesarnya alveoli dalam
kehamilan
f) Oksitosin, berfungsi mengencangkan otot halus dalam
rahim pada saat melahirkan dan pasca melahirkan oksitosin
juga mengencangkan otot halus disekitar alveoli untuk
memeras ASI menuju saluran susu. Oksitosin berperan
dalam proses turunnya susu let-down/milk ejection reflex
g) Human Placental Lactogen (HPL), sejak bulan kedua
kehamilan, plasenta mengeluarkan banyak HPL yang
berperan dalam pertumbuihan payudara, puting dan areola
sebelum melahirkan. Pada bukan kelima dan keenam
kehamilan, payudara siap memproduksi ASI (Mulyani,
2013).
172
5) Manfaat ASI
a) Bagi bayi
(1) Dapat membantu memulai kehidupannya dengan baik
Bayi yang mendapatkan ASI mempunyai kenaikan
berat badan yang baik setelah lahir, pertumbuhan
setelah periode perinatal baik, dan mengurangi
kemungkinan obesitas
(2) Mengandung antibodi
Mekanisme pembentukan antibodi pada bayi yaitu
apabila ibu mendapat infeksi maka tubuh ibu akan
membentuk antibodi dan akan disalurkan dengan
bantuan jaringan limposit. Antibodi di payudara disebut
mammae associated immunocompetent lymphoid tissue
(MALT). Kekebalan terhadap penyakit saluran
pernafasan yang ditransfer disebut Bronchus associated
immunocompetent lymphoid tissue (BALT) dan untuk
penyakit saluran pencernaan ditransfer melalui Gut
associated immunocompetent lymphoid tissue (GALT)
(3) ASI mengandung komposisi yang tepat
ASI merupakan sumber gizi yang sangat ideal dengan
komposisi yang seimbang dan disesuaikan dengan
kebutuhan pertumbuhan bayi. ASI adalah makanan
bayi yang paling sempurna, baik kualitas maupun
kuantitasnya dan sesuai dengan kebutuhan
pertumbuhan bayi.
(4) Memberi rasa nyaman dan aman pada bayi dan adanya
ikatan antara ibu dan bayi
Hubungan fisik ibu dan bayi baik untuk perkembangan
bayi, kontak kulit ibu ke kulit bayi yang mengakibatkan
perkembangan psikomotor maupun sosial yang lebih
baik.
173
(5) Terhindar dari alergi
Pada bayi baru lahir sistem IgE belum sempurna.
Pemberian susu formula akan merangsang aktivasi
sistem ini dan dapat menimbulkan alergi. ASI tidak
menimbulkan efek ini. Pemberian protein asing yang
ditunda sampai umur 6 bulan akan mengurangi
kemungkinan alergi.
(6) ASI meningkatkan kecerdasan bayi
Lemak pada ASI adalah lemak tak jenuh yang
mengandung omega 3 untuk pematangan sel-sel otak,
sehingga jaringan otak bayi yang mendapat asi
eksklusif akan tumbuh optimal dan terbebas dari
rangsangan kejang, sehingga menjadikan anak leih
cerdas dan terhindar dari kerusakan sel-sel saraf otak
(Suprijati, 2014).
b) Bagi ibu
(1) Mengurangi perdarahan setelah persalinan
Saat ibu menyusui terjadi peningkatan kadar oksitosin
yang berguna juga untuk penutupan pembuluh darah
sehingga perdarahan akan lebih cepat berhenti, hal ini
akan menurunkan angka kematian ibu yang melahirkan.
(2) Menjarangkan kehamilan
Menyusui merupakan cara kontrasepsi yang aman,
murah dan cukup berhasil.
(3) Lebih cepat langsing kembali
Menyusui memerlukan energi maka tubuh akan
mengambilnya dari lemak yang tertimbun selama
hamil. Dengan demikian berat badan ibu yang
menyusui akan lebih cepat kembali keberat badan
sebelum hamil.
174
(4) Mengurangi kemungkinan menderita kanker
Ibu yang memberikan ASI eksklusif pada umunya
kemungkinan menderita kanker payudar dan indung
telur berkurang.
(5) Memberi kepuasan pada ibu
Ibu yang berhasil memberikan ASI eksklusif akan
merasa puas dan merupakan kebanggaan yang
mendalam (Nugroho dkk, 2014).
c) Bagi Keluarga
(1) Lebih ekonomis
ASI tidak perlu dibeli, sehingga dana yang seharusnya
digunakan untuk membeli susu formula dapat
digunakan untuk keperluan lain. Penghematan juga
disebabkan karena bayi yang mendapat ASI lebih
jarang sakit sehingga mengurangi biaya berobat.
(2) Tidak merepotkan
Menyusui sangat praktis, karena dapat diberikan
dimana saja dan kapan saja. Keluarga tidak perlu
menyiapkan air masak, botol, dan dot yang harus
dibersihkan (Suprijati, 2014).
6) Komposisi Gizi dalam ASI
Komposisi ASI tidak sama dari waktu ke waktu, hal ini
berdasarkan stadium laktasi. Komposisi ASI dibedakan menjadi
3 macam yaitu:
a) Kolostrum
ASI yang dihasilkan pada hari pertama sampai hari ketiga
setelah bayi lahir. Kolostrum merupakan caira yang agak
kental berwarna kekuning-kuningan, lebih kuning
dibanding dengan ASI mature, bentuknya agak kasar karena
mengandung butiran lemak dan sel-sel epitel, dengan kasiat
kolostrum sebagai berikut:
175
(1) Sebagai pembersih selaput usus BBL sehingga saluran
pencernaan siap untuk menerima makanan
(2) Mengandung kadar protein yang tinggi terutama gama
globulin sehingga dapat memberikan perlindungan
tubuh terhadap infeksi
(3) Mengandung zat antibodi sehingga mampu melindungi
tubuh bayi dari berbagai penyakit infeksi untuk jangka
waktu sampai dengan 6 bulan
b) ASI masa transisi
ASI yang dihasilkan mulai dari hari ke-4 sampai hari ke-10
c) ASI mature
ASI yang dihasilkan mulai dari hari ke-10 sampai
seterusnya (Suprijati, 2014).
Tabel 2.11 Komposisi ASI
Kandungan Kolostrum Transisi Matur
Energi (Kg kla) 57,0 63,0 65,0
Laktosa (gr/100 ml) 6,5 6,7 7,0
Lemak (gr/100 ml) 2,9 3,6 3,8
Protein (gr/100 ml) 1,195 0,965 1,324
Mineral (gr/100 ml) 0,3 0,3 0,2
Imunoglobin :
Ig A (mg/100 ml) 335,9 - 119,6
Ig B (mg/100 ml) 5,9 - 2,9
Ig M (mg/100 ml) 17,1 - 2,9
Lisosim (mg/100 ml) 14,2-16,4 - 24,3-27,5
Laktoferin 420-520 - 250-270
Sumber: Suprijati, 2014, Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas, Bagian Proses Laktasi dan
Menyusui, Ponorogo, Halaman 92.
g. Komplikasi Pada Masa Nifas dan Penanganannya
1) Perdarahan pervaginam
Perdarahan pervaginam yang melebihi 500 ml setelah bersalin
didefinisikan sebagai perdarahan pasca persalinan. Terdapat
beberapa masalah mengenai definisi ini :
a) Perkiraan kehilangan darah biasanya tidak sebanyak yang
sebenarnya, kadang-kadang hanya setengah dari biasanya.
176
Darah tersebut bercampur dengan cairan amnion atau
dengan urine. darah juga tersebar pada spon, handuk dan
kain di dalam ember dan di lantai
b) Volume darah yang hilang juga bervariasi akibatnya sesuai
dengan kadar haemoglobin ibu. Seorang ibu dengan kadar
Hb normal akan dapat menyesuaikan diri terhadap
kehilangan darah yang akan berakibat fatal pada anemia.
Seorang ibu yang sehat dan tidak anemia pun dapat
mengalami akibat fatal dari kehilangan darah.
c) Perdarahan dapat terjadi dengan lambat untuk jangka waktu
beberapa jam dan kondisi ini dapat tidak dikenali sampai
terjadi syokPenilaian resiko pada saat antenatal tidak dapat
memperkirakan akan terjadinya perdarahan pasca
persalinan. Penanganan aktif kala III sebaiknya dilakukan
pada semua wanita yang bersalin karena hal ini dapat
menurunkan insiden perdarahan pasca persalinan akibat
atonia uteri. Semua ibu pasca bersalin harus dipantau
dengan ketat untuk mendiagnosis perdarahan fase
persalinan (Nugroho dkk, 2014).
2) Infeksi masa nifas
Beberapa bakteri dapat menyebabkan infeksi setelah persalinan.
Infeksi alat genital merupakan komplikasi masa nifas. Gejala
umum infeksi dapat dilihat dari temperature atau suhu
pembengkakan takikardi dan malaise. Sedangkan gejata lokal
dapat berupa uterus lembek, kemerahan, dan rasa nyeri pada
payudara atau adanya disuria. Ibu beresiko terjadi infeksi post
partum karena adanya luka pada bekas pelepasan plasenta,
laserasi pada saluran genital termasuk episiotomi pada
perineum, dinding vagina dan serviks, infeksi post SC yang
mungkin terjadi.
Penyebab infeksi : bakteri endogen dan bakteri eksogen
177
Faktor predisposisi : nutrisi yang buruk, defisiensi zat besi,
persalinan lama, ruptur membran, episiotomi, SC
Gejala klinis : endometritis tampak pada hari ke 3 post
partum disertai dengan suhu yang mencapai 39°C dan takikardi,
sakit kepala, kadang juga terdapat uterus yang lembek.
Manajemen : ibu harus diisolasi (Nugroho dkk, 2014).
3) Sakit kepala, nyeri epigastrik dan penglihatan kabur
Wanita yang baru melahirkan sering mengeluh sakit kepala
hebat atau penglihatan kabur. Penanganannya meliputi :
a) Jika ibu sadar periksa nadi, tekanan darah, pernafasan.
b) Jika ibu tidak bernafas periksa lakukan ventilasi dengan
masker dan balon. Lakukan intubasi jika perlu dan jika
pernafasan dangkal periksa dan bebaskan jalan nafas dan
beri oksigen 4-6 liter per menit.
c) Jika pasien tidak sadar/ koma bebaskan jalan nafas
baringkan pada sisi kiri, ukur suhu. periksa apakah ada kaku
tengkuk (Nugroho dkk, 2014).
4) Pembengkakan diwajah atau ekstremitas
a) Periksa adanya varises
b) Periksa kemerahan pada betis
c) Periksa apakah tulang kering, pergelangan kaki, kaki
oedema (Nugroho dkk, 2014).
5) Demam, muntah, rasa sakit waktu berkemih
Organisme yang menyebabkan infeksi saluran kemih berasal
dari flora normal perineum. Sekarang terdapat bukti bahwa
beberapa galur E. Coli memiliki pili yang meningkatkan
virulensinya. Pada masa nifas dini, sensitivitas kandung kemih
terhadap tegangan air kemih di dalam vesika sering menurun
akibat trauma persalinan serta analgesia epidural atau spinal.
Sensasi peregangan kandung kemih juga mungkin berkurang
akibat rasa tidak nyaman yang ditimbulkan oleh episiotomi yang
178
lebar, laserasi periuretra atau hematoma dinding vagina. Setelah
melahirkan terutama saat infuse oksitosin dihentikan terjadi
diuresis yang disertai peningkatan produksi urine dan distensi
kandung kemih. Overdistensi yang disertai kateterisasi untuk
mengeluarkan air yang sering menyebabkan infeksi saluran
kemih (Nugroho dkk, 2014).
6) Payudara yang berubah menjadi merah, panas, dan terasa sakit
Payudara bengkak yang tidak disusu secara adekuat dapat
menyebabkan payudara menjadi merah, panas. terasa sakit,
akhirnya terjadi mastitis. Puting lecet akan memudahkan
masuknya kuman dan terjadinya payudara bengkak. BH yang
terlatu ketat, mengakibatkan segmental engorgement. Kalau
tidak disusu dengan adekuat. bisa teriadi mastitis. Ibu yang diit
jelek. kurang istirahat, anemia akan mudah terkena infeksi.
Gejalanya meliputi :
a) Bengkak, nyeri seluruh payudara/nyeri lokal
b) Kemerahan pada seluruh payudara atau hanya local
c) Payudara keras dan berbenjol-benjol (merongkol)
d) Panas badan dan rasa sakit umum
Penatalaksanaannya meliputi :
a) Menyusui diteruskan. Pertama bayi disusukan pada
payudara yang terkena edema dan sesering mungkin, agar
payudara kosong kemudian pada payudara yang normal.
b) Berilah kompres panas. bisa menggunakan shower hangat
atau tap basah panas pada payudara yang terkena.
c) Ubahlah posisi menyusui dari waktu ke waktu, yaitu dengan
posisi tiduran. duduk atau posisi memegang bola (tootbalt
position)
d) Pakailah baju BH yang longgar
e) Istirahat yang cukup makanan yang bergizi
f) Banyak minum sekitar 2 liter per hari
179
Dengan cara-cara seperti tersebut di atas biasanya
peradangan akan menghilang setelah 48 jam, jarang sekali yang
menjadi abses. Tetapi apabila dengan cara-cara seperti tersebut
di atas tidak ada perbaikan setetah 12 jam maka diberikan
antibiotik selama 5-10 hari dan analgesia (Nugroho dkk, 2014).
7) Kehilangan nafsu makan
Sesudah anak lahir ibu akan merasa telah mungkin juga lemas
karena kehabisan tenaga. Hendaknya lekas berikan minuman
hangat, susu, kopi atau teh yang bergula. Apabila ibu
menghendaki makanan, berikanlah makanan yang sifatnya
ringan walaupun dalam persalinan lambung dan alat pencernaan
tidak langsung turut mengadakan proses persalinan, tetapi
sedikit atau banyak pasti dipengaruhi proses persalinannya
tersebut. Sehingga alat pencernaan perlu istirahat guna
memulihkan keadaannya kembali.
Oleh karena itu tidak benar bila ibu diberikan makanan
sebanyak-banyaknya walaupun ibu menginginkannya. Tetapi
biasanya disebabkan adanya kelelahan yang amat berat, nafsu
makan pun terganggu sehingga ibu tidak ingin makan (Nugroho
dkk, 2014).
8) Rasa sakit, merah,lunak dan pembengkakan dikaki
Selama masa nifas dapat terbentuk trhombus sementara pada
vena-vena manapun di pelvis yang mengalami dilatasi dan
mungkin lebih sering mengalaminya.
Faktor predisposisi :
a) Obesitas
b) Peningkatan umur maternal dan tingginya paritas
c) Riwayat sebelumnya mendukung
d) Anestesi dan pembedahan dengan kemungkinan trauma
yang lama pada keadaan pembuluh vena
e) Anemia maternal
180
f) Hypotermi dan penyakit jantung
g) Endometritis
h) Varicostitis
Manifestasi :
a) Timbul secara akut
b) Timbul rasa nyeri akibat terbakar
c) Nyeri tekan permukaan (Suprijati, 2014).
9) Merasa sedih atau tidak mampu mengasuh sendiri bayinya atau
dirinya sendiri
Pada minggu-minggu awal setelah persalinan kurang lebih 1
tahun ibu post partum cenderung akan mengalami perasaan-
perasaan yang tidak pada umumnya, seperti merasa sedih, tidak
mampu mengasuh dirinya sendiri dan bayinya.
Faktor penyebab :
a) Kekecewaan emosional yang mengikuti kegiatan bercampur
rasa takut yang di alami kebanyakan wanita selama hamil
dan melahirkan
b) Rasa nyeri pada awal masa nifas
c) Kelelahan akibat kurang tidur selama persalinan dan telah
melahirkan kebanyakan di rumah sakit
d) Kecemasan akan kemampuannya untuk merawat bayinya
setelah meninggalkan rumahsakit
e) Ketakutan akan menjadi tidak menarik lagi (Suprijati,
2014).
h. Tanda Bahaya Masa Nifas
1) Demam tinggi hingga melebihi 38°C
2) Perdarahan vagina yang luar biasa atau tiba-tiba bertambah
banyak (lebih dari perdarahan haid biasa atau bila memerlukan
penggantian pembalut 2 kali dalam setengah jam), disertai
gumpalan darah yang besar-besar dan berbau busuk.
181
3) Nyeri perut hebat/rasa sakit dibagian bawah abdomen atau
punggung, serta ulu hati.
4) Sakit kepala parah/terus menerus dan pandangan nanar/masalah
penglihatan
5) Pembengkakan pada wajah, jari-jari atau tangan
6) Rasa sakit, merah atau bengkak dibagian betis atau kaki
7) Payudara membengkak, kemerahan, lunak disertai demam
8) Puting payudara berdarah atau merekah, sehingga sulit untuk
menyusui
9) Tubuh lemas dan terasa seperti mau pingsan, merasa sangat letih
atau nafsu terengah-engah
10) Kehilangan nafsu makan dalam waktu lama
11) Tidak bisa buang air besar selama tiga hari atau rasa sakit waktu
buang air kecil
12) Merasa sangat sedih atau tidak mampu mengasuh bayinya atau
diri sendiri (Nugroho dkk, 2014).
i. Kunjungan Nifas
Pelayanan kesehatan bagi ibu sedikitnya 3 kali selama masa nifas
yaitu 1 kali pada periode 6 jam sampai 3 hari pascapersalinan, 1x
pada periode 4 hari sampai 28 hari pascapersalinan. 1 kali pada
periode 29 hari sampai dengan 42 hari pascapersalinan (Kemenkes
RI, 2014), dengan tujuan kunjungan sebagai berikut :
1) Kunjungan I (6 jam - 3 hari setelah persalinan), tujuannya yaitu:
a) Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri
b) Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan : rujuk
bila perdarahan berlanjut
c) Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota
keluarga bagaimana mencegah perdarahan masa nifas
karena atonia uteri
d) Pemberian ASI awal
e) Melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir
182
f) Menjaga bayi tetap sehat dengan mencegah hipotermi
2) Kunjungan II (4-28 hari setelah persalinan), tujuannya yaitu :
a) Memastikan involusi uterus berjalan normal: uterus
berkontraksi, fundus dibawah umbilikus, tidak ada
perdarahan abnormal dan tidak ada bau
b) Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi atau
perdarahan abnormal
c) Memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan dan
istirahat
d) Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak
memperlihatkan tanda-tanda penyulit
e) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada
bayi, tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat
bayi sehari-hari
3) Kunjungan III (29-42 hari setelah persalinan), tujuannya yaitu :
a) Menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang ia dan
bayi alami
b) Memberikan konseling KB secara dini (Walyani, E.S,
2015b).
j. Tujuan Asuhan Masa Nifas
Tujuan asuhan masa nifas meliputi :
1) Menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun
psikologis.
2) Melaksanakan skrinning secara komprehensif, deteksi dini,
mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu
maupun bayi.
3) Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan
diri, nutrisi, KB, cara dan manfaat menyusui, pemberian
imunisasi serta perawatan bayi sehari-hari.
4) Memberikan pelayanan keluarga berencana.
5) Mendapatkan kesehatan emosi (Nugroho dkk, 2014).
183
k. Standart Asuhan Nifas
Menurut Walyani (2015b), terdapat 3 standart pelayanan nifas yaitu:
1) Standar 13 : Perawatan Bayi Baru Lahir
Bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan
pernafasan spontan, mencegah asfiksia, menemukan kelainan
dan melakukan tindakan atau merujuk sesuai kebutuhan. Bidan
juga harus mencegah atau menangani hipotermi dan mencegah
hipoglikemia dan infeksi.
Hasil:
a) Bayi baru lahir dengan kelainan atau kecacatan dapat segera
menerima perawatan yang tepat
b) Bayi baru lahir mendapatkan perawatan yang tepat sehingga
dapat bernafas dengan baik
c) Penurunan angka kejadian hipotermi
2) Standar 14 : Penanganan Pada Dua Jam Pertama Setelah
Persalinan
Bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya
komplikasi paling sedikit selama 2 jam setelah persalinan, serta
melakukan tindakan yang diperlukan. Disamping itu, bidan
memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mempercepat
pulihnya kesehatan ibu, dan membantu ibu untuk memulai
pemberian ASI.
Hasil :
a) Komplikasi segera dideteksi dan dirujuk
b) Penurunan kejadian infeksi nifas dan neonatal
c) Penurunan kematian akibat perdarahan postpartum primer
d) Pemberian ASI dimulai dalam 2 jam pertama setelah
persalinan
3) Standar 15 : Pelayanan Bagi Ibu dan Bayi Pada Masa Nifas
Bidan memberikan pelayanan selama masa nifas di puskesmas
dan rumah sakit atau melakukan kunjungan ke rumah pada hari
184
ke-tiga, minggu ke 2 dan minggu ke 6 setelah persalinan, untuk
membantu proses penatalaksanaan tali pusat yang benar,
penemuaan dini, penatalaksanaan atau rujukan komplikasi yang
mungkin terjadi pada masa nifas, serta memberikan penjelasan
tentang kesehatan secara umum, kebersihan perorangan,
makanan bergizi, asuhan bayi baru lahir, pemberian ASI,
imunisasi dan KB.
Hasil :
a) Komplikasi pada masa nifas segera rujuk untuk penanganan
yang tepat
b) Mendorong pemberian ASI eksklusif
c) Menurunkan kejadian infeksi pada ibu dan bayi
d) Masyarakat menyadari pentingnya penjarangan kelahiran
e) Meningkatnya imunisasi pada bayi
2. Konsep Dasar Asuhan Kebidanan Masa Nifas
a. Pengkajian
Pengkajian atau pengumpulan data dasar adalah mengumpulkan
semua data yang dibutuhkan untuk mengevaluasi keadaan pasien.
Merupakan langkah pertama untuk mengumpulkan semua informasi
yang akurat dari semua sumber yang berkaitan dengan konsisi
pasien.
1) Data Subyektif
a) Biodata
(1) Nama
(2) Umur
(3) Agama
(4) Pendidikan
(5) Suku atau bangsa
(6) Pekerjaan
(7) Alamat
185
b) Keluhan utama
Mengetahui masaklah yang dihadapi yang berkaitan dengan
masa nifas, misalnya pasien merasa mules, sakit pada jalan
lahir karena adanya jahitan pada perenium.
c) Riwayat kesehatan
(1) Riwayat kesehatan yang lalu
Data ini di peroleh untuk mengetahui kemungkinana
adanya riwayat atau penyakit akut, kronis, seperti :
jantung, DM, hipertensi, asma, yang dapat
mempengaruhi pada masa nifas ini.
(2) Riwayat kesehatan sekarang
Data-data ini diperoleh untuk mengetahui adanya
penyakit yang diderita pada saat ini yang ada
hubungannya dengan masa nifas dan bayinya.
(3) Riwayat kesehatan keluarga
Data ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan
adanya pengearuh penyakit keluarga terhadap
gangguan kesehatan pasien dan bayinya, yaitu apabila
ada penyekit keluarga yang menyertai.
d) Riwayat perkawinan
Hal ini perlu dikaji ialah berapa kali menikah, ststus
menikah syah atau tidak, karena bila melahirkan tanpa
ststus yang jelas akan berkaitan dengan psikologisnya,
sehingga akan mempengaruhi proses nifas.
e) Riwayat Obstetrik
(1) Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu.
Berapa kali ibu hamil, apakah pernah aboryus, jumlah
anak, cara persalinan yang lalu, penolong persalinan,
keadaan nifas yang lalu.
186
(2) Riwayat persalinan sekarang
Tanggal persalinan, jenis persalinan, jenis kelamin
anak, keadaan bayi meliputi PB, BB, penolong
persalinan. Hal ni perlu dukaji untuk mengetahui
apakah proses persalinan mengalami kelainan atau
tidak yang biasa berpengaruh pada masa nifas saat ini.
f) Riwayat KB
Mengetahui apakah pasien pernah ikut KB dengan
kontrasepsi jenis apa, berapa lama, adakah keluhan selama
menggunakan kontrasepsi serta rencana KB setelah masa
nifas ini dan beralih ke kontrasepsi apa.
g) Kehidupan sosial budaya
Untuk mengetahui pasien dan keluarga yang mengenut adat
istiadat yang akan menguntungkan atau merugikan pasien
khususnya pada masa nifas. Misalnya pada kebiasaan
pantang makan.
h) Data psikososial
Untuk mengetahui respon ibu dan keluarga terhadap
bayinya. Wanita mengalami bayak perubahan emosi atau
psikologis selama masa nifas sementara ia menyesuaikan
diri menjadi seorang ibu. Cukup sering ibu menunjukkan
depresi ringan beberapa hari setelah kelahiran. Depresi
tersebut sering disebut sebagai postpartum blues.
Postpartum blues sebagian besar merupakan perwujudan
fenomena psikologis yang dialami oleh wanita yang
terpisah dari keluarga dan bayinya. Hal ini sering terjadi
oleh sejumlah faktor.
(1) Penyebab yang paling menonjol :
(a) Kekecewaan emosional yang megikuti rasa puas
dan takut yang dialami kebanyakan wanita selama
kehamilan dan persalinan.
187
(b) Rasa sakit masa nifas awal
(c) Kelelahan karena kurang tidur selama persalinan
dan postpartum
(d) Kecemasan merawat bayinya setelah meninggalkan
rumah sakit
(e) Rasa takut menjadi tidak menarik lagi bagi
suaminya.
(2) Menjelaskan pengkajian psikososial
(a) Respon keluarga terhadap ibu dan bayinya
(b) Respon ibu terhadap bayinya
(c) Respon ibu terhadap dirinya.
i) Data pengetahuan
Mengetahui seberapa jauh pengetahuan ibu tentang
perawatan setelah melahirkan sehingga akan
menggantungkan selama masa nifas.
j) Pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari
(1) Nutrisi, menggambarkan tentang pola makan dan
minum, frekuensi banyaknya, jenis makanan dan
makanan pantangan.
(2) Eliminasi, menggambrkan pola fungsi sekresi yaitu
kebiasaan buang air besar (frekuensi, jumlah,
konsistensi, dan bau), serta kebiasaan buang air kecil
(frekuensi, warna, dan jumlah).
(3) Istirahat, menggambarkan pola istirahat dan tidur klien,
berapa jam klien tidur, kebiasaan sebelum tidur.
Misalnya, membaca, mendengarkan musik, kebiasaan
mengkonsumsi obat tidur, kebiasaan tidur siang
pengguna waktu luang. Istirahat sangat penting bagi ibu
masa nifaskarena dengan istirahat yang cukup akan
mempercepat penyebuhan.
188
(4) Personal hygiene, dikaji untuk mengetahui apakah ibu
selalu menjaga kebersihan tubuh terutama pada daerah
genetalia, karena pada masa nifas masih mengeluarkan
lokhea.
(5) Aktivitas, menggambarkan pola aktivitas pasien sehari-
hari. Pada pola ini perlu dikaji pengearuh aktivitas
terhadap kesehatnnya. Mobilisasi sedini mungkin dapat
mempercepat proses pengembalian alat-alat reproduksi.
Apakah ibu melakukan ambulasi, seberapa sering,
apakah kesulitan, dengan bantuan atau sendiri, apakah
ibu pusing ketika melakukan ambulasi.
2) Data Obyektif
Dalam menghadapi masa nifas dari seorang klien, seorang bidan
harus mengumpulkan data untuk memastikan bahwa keadaan
klien dalam keadaan stabil. Yang termasuk dalam komponen-
komponen pengkajian data obyetif ini adalah :
a) Vital Sign
Vital Sign ditujuknan untuk mengetahui keaddan ibu
berkaitan dengan kondisi yang dialaminya.
b) Temperatur atau suhu
Peningkatan suhu badan mencapai pada 24 jam pertama
masa nifas pada umumnya disebabkan oleh dehidrasi, yang
disebabkan oleh keluarnya cairan pada waktu melahirkan,
selain itu bisa juga disebabkan karena istirahat dan tidur
yang diperpanjang selama awal persalinan. Tetapi pada
umumnya setelah 12 jam postpartum suhu tubuh kembali
normal. Kenaikan suhu yang mencapai > 38 °C adalah
mengarah ke tanda-tanda infeksi.
c) Nadi dan Pernapasan
(1) Nadi berkisar antara 60-80x//menit. Denyut nadi diatas
100x/menit pada masa nifas adalah mengidentifikasi
189
adanya suatu infeksi, hal ini salah satunya bisa
diakibatkaan oleh proses persalinan sulit atau karena
kehilangan darah yang berlebihan.
(2) Jika takikardi tidak disertai panas kemungkinan
disebabkan karena adanya vitium kardis. Beberapa ibu
postpartum kadang-kadang mengalami bradikardi
puerperal, yang denut nadinya mencapai serendah-
rendahnya 40 sampai 50x/menit. Beberapa alasan telah
diberikan sebagai penyebab yang mungkin, tetapi
belum ada penyelituan yang membuktikan bahwa hal iti
adalah suatu kelainan.
(3) Pernafasan harus berada dalam rentang yang normal,
yaitu sekitar 20-30x/menit.
d) Tekanan Darah
Pada beberapa kasus ditemukan keadaan hipertensi
postpartum, tetapi keadaan ini akan menghilang dengan
sendirinya apabila tidak ada penyakit lain yang
menyertainya dalam 2 bulan pengobatan.
e) Pemeriksaan Fisik
Pemeriksaan fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Menjelaskan pemeriksaan fisik :
(1) Keadaan payudara dan puting susu
(a) Simetris atau tidak
(b) Konsistensi, ada pembengkakan atau tidak
(c) Puting menonjol atau tidak, lecet atau tidak
(2) Keadaan abdomen
(a) Uterus
(b) Normal, apabila kokoh , berkontraksi baik, tinggi
fundus uteri (TFU) sesuai masa nifas.
(c) Abnormal. Aapabila lembek, diatas ketinggian
fundal saat masa postpartum segera
190
(d) Kandung kemih : bisa buang air atau tidak biasa
buang air
(3) Keadaan Genetalia
(a) Lokhea
1) Normal. Apabila warna merah hitam (rubra),
bau khas, tidak ada bekuan darah atau butir-
butir darah beku (ukuran jeruk kecil), jumlah
perdarahan yang ringan atau sedikit (hanya
perlu ganti pembalut setiap 3-5jam).
2) Abnormal. Apabila warna lokhea merah
terang, bau busuk, mengekuarkan darah beku,
perdarahan berat (memerlukan penggantian
pembalut setiap 0-2 jam)
(b) Keadaan perenium : odema, hematoma bekas luka
episiotomi atau robekan, hecting
(c) Keadaan anus : hemoroid
(d) Keadaan ekstermitas
b. Menyusun diagnosa
Mengidentifiksi diagnosa kebidanan dan masalah berdasarkan
interprestasi yang benar atau tas data-data yang telah dikumpulkan.
Dalam langkah ini data yang telah dikumpulkan diinterprestasikan
menjadi diagnosa kebidanan dan masalah. Keduanya digunakan
karena beberapa masalah atau tidak dapat diselesaikan seperti
diagnosa tetapi membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam
rencana asuhan terhadap pasien, masalah sering berkaitan dengan
pengalaman wanita yang diidentifikasi oleh bidan. Diagnosa dapat
ditegakkan yang berkaitan dengan para, abortus , anak hidup, umur
ibu, dan keadaan nifas.
Data dasar meliputi :
191
1) Data subyektif berupa pernyataan ibu tentang jumlah persalinan,
apakah pernah abortus atau tidak, keterangan ibu tentang umur,
keterangan ibu tentang keluhan.
2) Data obyektif berupa palpasi tentang TFU dan kontraksi, hasil
pemeriksaan tentang pengeluaran pervaginam, hasil
pemeriksaan tanda-tanda vital.
3) Masalah
Permasalahn yang muncul berdasarkan pernyataan pasien. Data
dasar meliputi :
a) Data subyektif berupa data yang didapat dari hasil anamnesa
pasien.
b) Data obyektif berupa data yang didapat dari hasil
pemeriksaan diagnosa.
Selanjutnya mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial yang
mungkin akan terjadi. Pada langkah ini diidentifikasi masalah atau
diagnose potensial berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa. Hal
ini membutuhkan antisipasi, pencegahan, bila memungkinkan
menunggu mengamati dan bersiap-siap apabila hal tersebut benar-
benar tejadi. Melakukan asuhan yang aman penting sekali dalam hal
ini.Langkah ini memerlukan kesinambungan dari manajemen
kebidanan. Identifikasi dan menetapkan perlunya tindakan segera
oleh bidan atau dokter dan atau untuk dikonsultasikan atau ditangani
bersama dengan anggota tim kesehatan lain sesuai dengan kondisi
pasien.
c. Merencanakan asuhan kebidanan
Langkah ini ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya yang
merupakan lanjutan dari masalah atau diagnosa yang telah
dididentifikasi atau di antisipasi. Rencana asuhan yang menyeluruh
tidak hanya meliputi apa yang sudah dilihat dari konsisi pasien atau
dari setiap masalah yang berkaitan, tetapi juga berkaitan dengan
kerangka pedoman antisipasi bagi wanita tersebut yaitu apa yang
192
akan terjadi berikutnya. Penyuluhan, konseling dari rujukan untuk
masalah-masalah sosial, ekonomi atau masalah psikososial. Adapun
hal-hal yang perlu dilakukan pada kasus ini adalah :
1) Observasi
Meliputi keadaan umum, kesadaran, tanda-tanda vital, TFU,
kontraksi uterus, anjurkan ibu untuk segera berkemih, observasi
mobilisasi dini, jelaskan manfaatnya dan perdarahan.
Menganjurkan pada ibu untuk kembali mengerjakan pekerjaan
sehari-hari.
2) Kebersihan Diri
a) Jaga kebersihan seluruh tubuh terutama daerah genetalia.
b) Ganti pembalut minimal 2 kali sehari atau setiap kali selesai.
3) Istirahat
a) Beri pengertian manfaat istirahat
b) Kembali mengerjakan pekerjaan sehari-hari.
4) Gizi
a) Mengkonsumsi makanan yang bergizi, bermutu dan cukup
kalori, sebaiknya ibu makan makanan yang mengandung
protein, vitamin dan mineral.
b) Minum sedikitnya 3 liter air sehari-hari atau segelas setiap
habis menyusui.
c) Minum tablet Fe/zat besi selama 40 hari pasca persalinan.
d) Minum vitamin A (200.000 unit) agar dapat memberikan
vitamin A kepada bayinya melalui ASI.
5) Perawatan Payudara
a) Menjaga kebersihan payudara
b) Memberi ASI ekslusif sampai bayi umur 6 bulan
6) Hubungan Seksual
Memberi pengertian hubungan seksual kapan boleh dilakukan
7) Keluarga Berencana
193
Menganjurkan ibu untuk segera mengikuti KB setalah masa
nifas terlewati sesuai dengan keinginannya. Asuhan penyuluhan
pada klien dan keluarga. Mengarahkan atau melaksanakan
rencana asuhan secara efesien dan aman.
d. Melaksanakan asuhan kebidanan
Langkah-langkah ini merupakan tindak lanjut dari perencanaan tapi
tidak semua perencanaan dilaksanakan.
e. Evaluasi
Langkah ini merupakan langkah terakhir guna mengetahui apa yang
telah dilakukan bidan. Mengevaluasi keefektifan dari asuhan yang
diberikan, ulangi kembali proses manajemen dengan benar terhadap
setiap aspek asuhan yang sudah dilaksanakan tapi belum efektif atau
merencanakan kembali yang belum terlaksana. (Sutanto,2018).
f. Dokumentasi SOAP
Model dokumentasi yang digunakan dalam asuhan kebidanan yaitu
dalam bentuk catatan perkembangan karena bentuk asuhan yang
diberikan berkesinambungan dan menggunakan proses yang terus
menerus dengan menggunakan subjektif, objektif, analisis, dan
penatalaksanaan (SOAP) yang merupakan salah satu metode
pendokumentasian.
1) S = Subjektif
Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data
klien melalui anamnesis antara lain tanggal, tahun, waktu,
biodata, riwayat, termasuk kondisi klien. Catatan data spesifik
atau fokus. Tanda dan gejala subjektif yang didapatkan dari
hasil bertanya pada klien, suami dan keluarga. Catatan ini
berhubungan dengan masalah sudut pandang klien. Ekspresi
klien mengenai kekhawatiran dan keluhannya dicatat sebagai
kutipan langsung atau ringkasan yang berhubungan dengan
diagnosa.
194
2) O = Objektif
Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data
klien melalui pengamatan dan terukur, pemeriksaan fisik klien
didapatkan melalui inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi,
termasuk data penunjang. Data ini memberikan bukti gejala
klinis klien dan fakta yang berhubungan dengan diagnosa.
3) A = Analisis
Menggambarkan pendokumentasian hasil analisis, diagnosis,
dan masalah kebidanan.
4) P = Penatalaksanaan
Mencatat seluruh perencanaan dan penatalaksanaan yang telah
dilakukan, misalnya tindakan antisipatif, tindakan segera,
tindakan secara komprehensif, penyuluhan, dukungan,
kolaborasi, evaluasi/follow up dan rujukan. Dokumentasi
menunjukkan perencanaan yang tepat (Astuti dkk, 2017).
D. Neonatus
1. Konsep Dasar Neonatus
a. Pengertian
Bayi baru lahir normal adalah bayi yang baru lahir pada usia
kehamilan genap 37-41 minggu, dengan presentasi belakang kepala
atau letak sungsang yang melewati vagina tanpa memakai alat.
Neonatus adalah bayi baru lahir yang menyesuaikan diri dari
kehidupan di dalam uterus ke kehidupan di luar uterus (Tando,
2016).
Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir pada usia
kehamilan 37-42 minggu dengan berat lahir 2500-4000 gram
(Sondakh, 2013).
Bayi baru lahir (Neonatus) adalah bayi yang baru mengalami
proses kelahiran, berusia 0 - 28 hari (Marmi dan Rahardjo, 2015).
195
b. Adaptasi Fisiologi Neonatus
Saat lahir, bayi harus beradaptasi dengan keadaan yang sangat
bergantung sampai menjadi mandiri. Banyak perubahan yang
dialami oleh bayi yang semula berada dalam lingkungan rahim ke
lingkungan luar rahim. Kemampuan adaptasi fisiologis bayi baru
lahir disebut juga homeostasis. Homeostatis neonatus ditentukan
oleh keseimbangan antara maturitas dan status gizi. Adaptasi
neonatus meliputi :
1) Adaptasi ekstra uterus yang terjadi cepat
a) Adaptasi sistem pernafasan
Sistem pernafasan adalah sistem yang paling tertantang
ketika terjadi perubahan di lingkungan intrauterin ke
lingkungan ekstrauterin. Organ yang bertanggungjawab
untuk oksigenasi janin sebelum bayi lahir adalah plasenta.
Pernafasan pertama pada bayi baru lahir normal terjadi
dalam waktu 30 menit pertama sesudah bayi lahir. Selain
adanya surfaktan, usaha bayi pertama kali untuk
mempertahankan tekanan alveoli adalah menarik napas dan
mengeluarkan napas dengan merinth sehingga udara
tertahan di dalam. Respirasi pada neonatus biasanya adalah
pernapasan diafragma dan abdomen, sedangkan frekuensi
dan kedalaman pernapasan belum teratur. Apabila surfaktan
berkurang, alveoli akan kolaps dan paru-paru kaku sehingga
terjadi atelektasis. Dalam keadaan anoksia, neonatus masih
dapat mempertahankan hidupnya karena adanya kelanjutan
metabolisme anaerob.
Saat kepala bayi melewati jalan lahir, bayi mengalami
penekanan yang tinggi pada toraksnya, dan tekanan ini akan
hilang dengan tiba-tiba setelah bayi lahir. Proses mekanis
ini menyebabkan cairan yang ada di dalam paru-paru hilang
karena terdorong ke bagian perifer paru yang kemudian
196
diabsorbsi. Karena terstimulasi oleh sensor kimia, suhu,dan
mekanis, akhirnya bayi memulai aktivasi napas untuk
pertama kali. Tekanan intratoraks yang negatif disertai
aktivasi napas yang pertama memungkinkan udara masuk
ke dalam paru-paru. Setelah beberapa kali napas, udara dari
luar mulai mengisi jalan napas pada trakea dan bronkus dan
akhirnya semua alveolus mengembang karena terisi udara.
Fungsi alveolus dapat maksimal jika dalam paru-paru bayi
terdapat surfaktan yang adekuat. Surfaktan membantu
menstabilkan dinding alveolus sehingga alveolus tidak
kolaps saat akhir napas (Tando, 2016).
b) Adaptasi sistem sirkulasi
Aliran darah dari plasenta berhenti pada saat tali pusat
diklem. Tindakan ini meniadakan suplai oksigen plasenta
dan menyebabkan terjadinya reaksi dalam paru sebagai
respons terhadap tarikan napas pertama. Setelah lahir, darah
BBL harus melewati paru untuk mengambil oksigen dan
bersirkulasi melalui tubuh guna mengantarkan oksigen ke
seluruh jaringan. Agar sirkulasi baik, harus terjadi dua
perubahan besar dalam kehidupan di luar rahim, yaitu
penutupan foramen ovale pada atrium jantung dan
perubahan duktus arteriosus antara paru-paru dan aorta.
Perubahan sirkulasi ini terjadi akibat perubahan tekanan
pada seluruh sistem pembuluh darah. Oksigen
menyebabkan sistem pembuluh darah mengubah tekanan
dengan cara mengurangi/meningkatkan resistensinya
sehingga mengubah aliran darah. Dua peristiwa yang
mengubah sistem pembuluh darah, yaitu sebagai berikut :
(1) Pada saat tali pusat dipotong, resistensi pembuluh
sistemik meningkat dan tekanan atrium kanan menurun
karena berkurangnya aliran darah ke atrium kanan
197
tersebut. Hal ini menyebabkan penurunan volume dan
tekanan atrium kanan itu sendiri. Dua kejadian ini
membantu darah dengan kandungan oksigen sedikit
mengalir ke paru-paru untuk menjalani proses
oksigenasi ulang.
(2) Pernapasan pertama mengurangi resistensi pembuluh
darah paru-paru dan meningkatkan tekanan atrium
kanan sehingga menimbulkan relaksasi dan terbukanya
sistem pembuluh darah paru. Peningkatan sirkulasi ke
paru-paru mengakibatkan peningkatan volume dara dan
tekanan atrium kanan. Karena peningkatan tekanan
atrium kanan dan penurunan tekanan atrium kiri,
foramen ovale secara fungsional menutup.
Dalam beberapa saat, perubahan yang luar biasa terjadi
pada jantung dan sirkulasi darah bayi baru lahir. Walaupun
perubahan ini tidak selesai secara anatomis dalam beberapa
minggu, penutupan fungsional foramen ovale dan duktus
arteriosus terjadi setelah bayi lahir ( Tando, 2016).
c) Adaptasi suhu
Bayi baru lahir memiliki kecenderungan cepat stres karena
perubahan lingkungan dan bayi harus beradaptasi dengan
suhu lingkungan yang cenderung dingin di luar. Terdapat
empat mekanisme kemungkinan hilangnya panas tubuh dari
bayi baru lahir ke lingkungannya. Sesaat sesudah lahir, bayi
berada di tempat yang suhunya lebih rendah daripada dalam
kandungan dan dalam keadaan basah. Jika dibiarkan dalam
suhu kamar 25°C, bayi akan kehilangan panas melalui
evaporasi, konduksi, konveksi, dan radiasi sebanyak 200
kalori/kg BB/menit, yaitu sebagai berikut :
(1) Konduksi, panas dihantarkan dari tubuh bayi ke benda
di sekitarnya yang kontak langsung dengan tubuh bayi.
198
(2) Konveksi, panas hilang dari tubuh bayi ke udara di
sekitarnya yang sedang bergerak. Contoh: membiarkan
bayi terlentang di ruang yang relatif dingin.
(3) Radiasi, panas dipancarkan dari tubuh bayi, ke luar
tubuhnya ke lingkungan yang lebih dingin. Contoh:
bayi baru lahir dibiarkan dalam keadaan telanjang.
(4) Evaporasi, panas yang hilang melalui proses penguapan
karena kecepatan dan kelembapan udara. Contoh: bayi
baru lahir yang tidak dikeringkan dari cairan amnion.
Untuk itu, bidan harus melakukan pencegahan
kehilangan panas dengan segera mengeringkan tubuh bayi
dari cairan amnion, menyelimuti bayi, menempatkan bayi di
tempat yang hangat, dan jangan menggunakan stetoskop
dingin untuk memeriksa bayi.
Sumber termoregulasi yang digunakan bayi baru lahir
adalah penggunaan lemak cokelat. Lemak cokelat berada di
daerah skapula bagian dalam, di sekitar leher, aksila, sekitar
toraks, di sepanjang kolumna vertebralis, dan sekitar ginjal.
Panas yang dihasilkan dari aktivitas lipid dalam lemak
cokelat dapat menghangatkan bayi baru lahir dengan
meningkatkan produksi panas hingga 100%. Cadangan
lemak cokelat lebih banyak terdapat pada bayi baru lahir
cukup bulan dibandingkan bayi lahir prematur. Lemak
cokelat tidak dapat diproduksi kembali oleh bayi baru lahir.
Cadangan lemak cokelat akan habis dalam waktu singkat
dengan adanya stres dingin.
Tiga faktor yang paling berperan dalam kehilangan
panas tubuh bayi, yaitu luas permukaan tubuh bayi, pusat
pengaturan suhu tubuh bayi yang belum berfungsi secara
sempurna, dan tubuh bayi terlalu kecil untuk memproduksi
dan menyimpan panas. Jika bayi kedinginan, bayi mulai
199
mengalami hipoglikemia, hipoksia, dan asidosis. Suhu
tubuh normal pada neonatus adalah 36,5°C-37,5°C melalui
pengukuran di aksila. Jika nilainya turun dibawah 36,5°C,
bayi mengalami hipotermia.
Hipotermia dapat terjadi setiap saat apabila suhu di
sekeliling bayi rendah dan upaya mempertahankan suhu
tubuh tidak dilakukan secara tepat, terutama pada masa
stabilisasi, yaitu 0-6 jam pertama setelah lahir. Hipotermia
menyebabkan perubahan metabolisme tubuh yang berakhir
dengan kegagalan fungsi jantung, perdarahan terutama pada
paru-paru, ikterus, dan kematian. Gejala hipotermi, yaitu
sebagai berikut:
(1) Sejalan dengan penurunan suhu tubuh, bayi menajdi
kurang aktif, letargi, hipotonus, tidak kuat mengisap
ASI dan menangis lemah.
(2) Pernapasan megap-megap dan lambat dan denyut
jantung menurun.
(3) Timbul sklerema, kulit mengeras berwarna kemerahan
terutama di bagian punggung, tungkai, dan lengan.
(4) Wajah bayi berwarna merah terang (Tando, 2016).
Gambar 2.7 Mekanisme kehilangan Panas pada Bayi Baru Lahir Sumber: Naomy Marie Tando, 2016. Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi dan Anak
Balita, Bagian Adaptasi Suhu, Jakarta, halaman 32.
200
d) Adaptasi sistem pencernaan
Pada saat masih dalam kandungan, janin melakukan
kegiatan mengisap dan menelan pada usia kehamilan aterm,
sedangkan refleks gumoh dan batuk baru terbentuk pada
saat persalina. Refleks mengisap dan menelan ASI sudah
dapat dilakukan bayi saat bayi diberikan kepada ibunya
untuk menyusu. Refleks ini terjadi akibat adanya sentuhan
pada langit-langit mulut bayi yang memicu bayi untuk
mengisap dan adanya kerja peristaltik lidah dan rahang
yang memeras air susu dan payudara ke kerongkongan bayi
sehingga memicu refleks menelan. Kemampuan bayi baru
lahir cukup bulan dalam menelan dan mencerna makanan
selain ASI masih terbatas. Kemampuan sistem pencernaan
untuk mencerna protein, lemak, dan karbohidrat belum
efektif. hubungan antara esofagus bawah dan lambung
belum sempurna sehingga sering menimbulkan gumoh pada
bayi baru lahir apabila mendapatkan ASI terlalu banyak
yang melebihi kapasitas lambung (Tando, 2016).
Bayi baru lahir yang tidak dapat mencerna makanan
dalam jumlah yang cukup akan membuat glukosa dari
glikogen (glikogenesis). Untuk memfungsikan otak, bayi
baru lahir memerlukan glukosa dalam jumlah tertentu.
Setelah tindakan tali pusat dengan klem pada saat kahir,
seorang bayi harus mulai mempertahankan glukosa
darahnya sendiri. Pada setiap bayi baru lahir glukosa darah
akan turun dalam waktu cepat (1-2 jam). Oleh karena kadar
gula darah tali pusat yang 65mg/100ml akan menurun
menjadi 50mg/100ml dalam waktu 2 jam setelah lahir,
energi tambahan yang diperlukan neonatus pada jam-jam
pertama sesudah lahir diambil dari hasil metabolisme asam
lemak sehingga kadar gula darah dapat mencapai
201
120mg/100ml. Bila perubahan glukosa menjadi glikogen
meningkat atau adanya gangguan pada metabolisme asam
lemak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan neonatus,
maka kemungkinan besar bayi akan mengalami
hipoglikemia. Gejala-gejala hipoglikemia bisa tidak jelas
dan tidak khusus meliputi kejang-kejang secara halus,
sianosis, apnea, menangis lemah, letargi, lunglai, dan
menolak makanan. Akibat jangka panjang hipoglikemia
ialah kerusakan yang meluas di seluruh sel-sel otak
(Walyani dan Purwoastuti, 2015).
2) Adaptasi di luar uterus yang terjadi secara kontinu
a) Perubahan sistem imun
Sistem imunitas bayi baru lahir masih belum matang,
sehingga menyebabkan neonatus rentan terhadap berbagai
infeksi dan alergi sistem imunitas yang matang akan
memberikan kekebalan alami dan kekebalan yang didapat.
Kekebalan alami terdiri dari struktur pertahanan tubuh yang
berfungsi mencegah atau meminimalkan infeksi. Berikut
beberapa contoh kekebalan alami:
(1) Perlindungan dari membran mukosa
(2) Fungsi saringan saluran napas
(3) Pembentukan koloni mikroba dikulit dan usus
(4) Perlindungan kimia oleh lingkungan asam lambung
Kekebalan alami juga disediakan pada tingkat sel oleh
sel darah yang membantu bayi baru lahir membunuh
mikroorganisme asing, tetapi sel-sel darah ini masih belum
matang artinya BBL tersebut belum mampu melokalisasi
dan memerangi infeksi secara efisien. Kekebalan yang
didapat akan muncul kemudian.
BBL dengan kekebalan pasif mengandung banyak virus
dalam tubuh ibunya. Reaksi anti bodi keseluruhan terhadap
202
antigen asing masih belum bisa dilakukan sampai awal
kehidupannya. Salah satu tugas utama selama masa bayi
dan balita adalah pembentukan sistem kekebalan tubuh.
Karena adanya defisiensi kekebalan alami yang didapat ini,
BBL sangat rentan terhadap infeksi. Reaksi BBL terhadap
infeksi masih lemah dan tidak memadai, oleh karena itu
pencegahan terhadap mikroba (seperti pada praktek
persalinan yang aman dan menyusui ASI dini terutama
kolostrum) dan deteksi dini serta pengobatan dini infeksi
menjadi sangat penting (Walyani dan Purwoastuti, 2016).
b) Perubahan pada darah
(1) Kadar Hemoglobin (Hb)
Bayi dilahirkan dengan kadar Hb yang tinggi.
Konsentrasi Hb normal adalah 13,7-20 g%. Hb
dominan pada bayi adalah hemoglobin F yang secara
bertahap mengalami penurunan selama satu bulan. Hb
bayi memiliki daya ikat (afinitas) yang tinggi terhadap
oksigen. Hal ini merupakan efek yang menguntungkan
bagi bayi. Selama beberapa hari kehidupan, kadar Hb
meningkat, sedangkan volume plasma menurun. Akibat
penurunan volume plasma tersebut, kadar hematokrit
(Ht) mengalami peningkatan. Kadar Hb selanjutnya
mengalami penurunan secara terus-menerus selama 7-9
minggu. Kadar Hb bayi usia 2 bulan normal adalah 12
g% (Walyani dan Purwoastuti, 2016).
(2) Sel darah merah
Sel darah merah bayi baru lahir memiliki usia yang
sangat singkat (80 hari) jika dibandingkan orang
dewasa (120 hari). Pergantian sel yang sangat cepat ini
menghasilkan lebih banyak sampah metabolik,
termasuk bilirubin yang harus dimetabolisme. Kadar
203
bilirubin yang berlebihan ini menyebabkan ikterus
fisiologis yang terlihat pada bayi baru lahir. Oleh sebab
itu, ditemukan hitung retikulosit yang tinggi pada bayi
baru lahir. Hal ini menggambarkan adanya
pembentukan sel darah merah dalam jumlah yang
tinggi (Walyani dan Purwoastuti, 2016).
(3) Sel darah putih
Jumlah sel darah putih rata-rata pada bayi baru
lahir adalah 10.000-30.000/mm². Peningkatan jumlah
sel darah putih lebih lanjut dapat terjadi pada bayi baur
lahir normal selama 24 jam pertama kehidupan. Periode
menangis yang lama juga dapat menyebabkan hitung
sel darah putih meningkat (Walyani dan Purwoastuti,
2016).
c) Perubahan gastrointestinal
Sebelum lahir, janin cukup bulan akan mulai
menghisap dan menelan. Refleks muntah dan refleks batuk
yang matang sudah terbentuk dengan baik pada saat lahir.
Kemampuan bayi baru lahir cukup bulan untuk menelan
dan mencerna makanan (selain susu) masih terbatas.
Hubungan antara esofagus bawah dan lambung masih
belum sempurna yang mengakibatkan “gumoh” pada bayi
baru lahir dan neonatus. Kapasitas lambung sendiri sangat
terbatas yaitu kurang dari 30 cc untuk seorang bayi baru
lahir cukup bulan, dan kapasitas lambung ini akan
bertambah secara lambat bersamaan dengan
pertumbuhannya.
Dengan adanya kapasitas lambung yang masih terbatas
ini akan sangat penting bagi pasien untuk mengatur pola
intake cairan pada bayi dengan frekuensi sedikit tapi sering,
contohnya memberi ASI sesuai keinginan bayi. Usu bayi
204
masih belum matang sehingga tidak mampu
melindungidirinya sendiri dari zat-zat berbahaya yang
masuk ke dalam saluran pencernaannya. Di samping itu
bayi baru lahir juga belum dapat mempertahankan air secara
efisien dibanding dengan orang dewasa, sehingga kondisi
ini dapat menyebabkan diare yang lebih serius pada
neonatus (Walyani dan Purwoastuti, 2016).
d) Perubahan sistem ginjal
BBL cukup bulan mengalami beberapa defisit
struktural dan fungsional pada sistem ginjal. Banyak
kejadian defisit tersebut membaik pada bulan pertama
kehidupan dan menjadi satu-satunya masalah pada bayi
baru lahir yang sakit atau mengalami stres. Keterbatasan
fungsi ginjal menjadi konsekuensi khusus jika bayi baru
lahir memerlukan cairan intravena atau obat-obatan yang
meningkatkan kemungkinan kelebihan cairan.
Ginjal bayi baru lahir menunjukkan penurunan aliran
darah ginjal dan penurunan kecepatan filtrasi glomerulus.
Kondisi ini mudah menyebabkan retensi cairan dan
intoksikasi air. Fungsi tubulus tidak matur sehingga dapat
menyebabkan kehilangan natrium dalam jumlah besar dan
ketidakseimbangan elekrolit lain. Bayi baru lahir tidak
dapat mengonsentrasikan urine dengan baik yang tercermin
dari berat jenis urine (1,004) dan osmomalitas urine yang
rendah. Semua keterbatasan ginjal ini lebih buruk pada bayi
kurang bulan.
BBL mengekskresikan sedikit urine pada 48 jam
pertama kehidupan, yaitu hanya 30-60 ml. Normalnya
dalam urine tidak terdapat protein atau darah. Debris sel
yang banyak dapat mengindikasikan adanya cedera atau
iritasi dalam sistem ginjal. Bidan harus ingat bahwa adanya
205
masa abdomen yang ditemukan pada pemeriksaan fisik
sering kali adalah ginjal dan dapat mencerminkan adanya
tumor, pembesaran, dan penyimpangan pada ginjal
(Walyani dan Purwoastuti, 2016).
e) Perlindungan Termal
Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan
kehilangan panas tubuh bayi baru lahir adalah sebagai
berikut:
(1) Hangatkan dahulu setiap selimut, topi, pakaian dan
kaos kaki bayi sebelum kelahiran
(2) Segera keringkan BBL
(3) Hangatkan dahulu area resusitasi BBL
(4) Atur suhu ruangan kelahiran pada suhu 24°C
(5) Jangan lakukan pengisapan pada bayi baru lahir di atas
alas tempat tidur yang basah
(6) Tunda memandikan BBL sampai suhunya stabil selama
2 jam atau lebih
(7) Atur agar ruangan perawatan bayi baru lahir jauh dari
jendela, pintu, lubang ventilasi atau pintu keluar
(8) Pertahankan kepala bayi baru lahir tetap tertutup dan
badannya dibedong dengan baik selama 48 jam pertama
(Walyani dan Purwoastuti, 2016).
3) Pemeliharaan Pernafasan
a) Stimulasi Taktil
Realisasi dari langkah ini adalah dengan mengeringkan
badan bayi segera setelah lahir dan melakukan masasse
pada punggung. Jika observasi nafas bayi belum maksimal,
lakukan stimulasi pada telapak kaki dengan menjentikkan
ujung jari tangan penolong.
206
b) Mempertahankan suhu hangat untuk bayi
Suhu yang hangat akan sangat membantu menstabilkan
upaya bayi dalam bernafas. Letakkan bayi di atas tubuh
pasien yang tidak ditutupi kain (dalam keadaan telanjang),
kemudia tutupi keduanya dengan selimut yang telah
dihangatkan terlebih dahulu. Jika ruangan ber-AC, sorotkan
lampu penghangat kepada pasien dan bayinya.
c) Menghindari prosedur yang tidak perlu
Ketika melakukan perawatan bayi baru lahir, hindari
prosedur yang sebenarnya tidak perlu dilakukan seperti:
(1) Menghisap lendir yang ada di salura napas bayi,
padahal bayi sudah berhasil menangis dan melakukan
napas pertamanya
(2) Melakukan stimulasi taktil yang berlebihan, menampar
pipi bayi baru lahir
(3) Memandikan bayi segera setelah lahir
(4) Melakukan pemeriksaan fisik kepada bayi dalam satu
jam pertama kelahiran. Sebaiknya biarkan bayi diatas
perut pasien untuk melakukan inisiasi dini dan
menstabilkan suhu tubuhnya melalui radiasi panas
tubuhnya (Walyani dan Purwoastuti, 2016).
c. Ciri-Ciri Bayi Baru Lahir Normal
1) Berat badan 2.500-4.000 gram.
2) Panjang badan 48-52 cm.
3) Lingkar dada 30-38 cm.
4) Lingkar kepala 33-35 cm.
5) Frekuensi jantung 120-160 kali/menit.
6) Pernapasan 40-60 kali/menit.
7) Kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan
cukup.
207
8) Rambut lanugo tidak terlihat, rambut kepala biasanya telah
sempurna.
9) Kuku agak panjang dan lemas.
10) Genitalia pada perempuan, labia mayora menutupi labia minora
sedangkan pada bayi laki-laki testis sudah turun, skrotum sudah
ada.
11) Refleks isap dan menelan sudah terbentuk dengan baik.
12) Refleks Moro atau gerak memeluk jika dikagetkan sudah baik.
13) Refleks grasp atau menggenggam sudah baik.
14) Eliminasi baik, mekonium keluar dalam 24 jam pertama,
mekonium berwarna hitam kecoklatan (Tando, 2016).
d. Klasifikasi Neonatus
1) Klasifikasi neonatus menurut masa gestasi:
a) Kurang bulan (preterm infant) : kurang 259 hari (37
minggu)
b) Cukup bulan (aterm infant) : 259 sampai 294 hari (37-42
minggu)
c) Lebih bulan (postterm infant) : lebih dari 294 hari (42
minggu) atau lebih
2) Klasifikasi neonatus menurut berat lahir:
a) Berat lahir rendah : kurang dari 2500 g
b) Berat lahir cukup : antara 2500 sampai 4000 g
c) Berat lahir lebih : lebih dari 4000 g
3) Klasifikasi menurut berat lahir terhadap masa gestasi
dideskripsikan masa gestasi dan ukuran berat lahir yang sesuai
untuk masa kehamilannya :
a) Neonatus cukup/kurang/lebih bulan (NCB/NKB/NLB)
b) Sesuai/kecil/besar untuk masa kehamilan
(SMK/KMK/BMK) (Marmi dan Rahardjo, 2015).
208
e. Reflek
Menurut Sondakh (2013) reflek pada bayi meliputi:
1) Rooting dan menghisap
Respons normal : bayi baru lahir menolehkan kepala ke arah
stimulus, membuka mulut, dan mulai mengisap bila pipi, bibir,
atau sudut mulut bayi disentuh dengan jari atau puting.
Respons abnormal : respons yang lemah atau tidak ada respons
terjadi pada prematuritas, penurunan atau cedera neurologis,
atau depresi sistem saraf pusat (SSP).
2) Menelan
Respons normal : bayi baru lahir menelan berkoordinasi dengan
menghisap bila cairan ditaruh di belakang lidah.
Respons abnormal : muntah, batuk, atau regurgitasi cairan dapat
terjadi kemungkinan berhubungan dengan sianosis sekunder
karena prematuritas, defisit neurologis, atau cedera terutama
terlihat setelah laringoskopi.
3) Ekstrusi
Respons normal : bayi baru lahir, menjulurkan lidah keluar bila
ujung lidah disentuh dengan jari atau puting.
Respons abnormal : ekstrusi lidah secara kontinu atau
menjulurkan lidah yang berulang-ulang terjadi pada kelainan
SSP dan kejang.
4) Moro
Respons normal : ekstensi simetris bilateral dan abduksi seluruh
ekstremitas dengan ibu jari dan jari telunjuk membentuk huruf
“c” diikuti dengan adduksi ekstremitas dan kembali ke fleksi
relaks jika posisi bayi berubah tiba-tiba atau jika bayi diletakkan
telentang pada permukaan yang datar.
Respons abnormal : respons asimetris terlihat pada cedera saraf
perifer (pleksus brakialis) atau fraktur klavikula atau fraktur
tulang panjang lengan atau kaki.
209
5) Melangkah
Respons normal : bayi akan melangkah dengan satu kaki dan
kemudian kaki lainnya dengan gerakan berjalan bila satu kaki
disentuh pada permukaan rata.
Respons abnormal : respons asimetris terlihat pada cedera saraf
SSP atau perifer atau fraktur tulang panjang kaki.
6) Merangkak
Respons normal : bayi akan berusaha untuk merangkak ke depan
dengan kedua tangan dan kaki bila diletakkan telungkup pada
permukaan datar.
Respons abnormal : respons asimetris terlihat pada cedera saraf
SSP dan gangguan neurologis.
7) Tonik leher atau fencing
Respons normal : ekstremitas pada satu sisi dimana saat kepala
ditolehkan akan ekstensi dan ekstremitas yang berlawanan akan
fleksi bila kepala bayi ditolehkan ke satu sisi selagi beristirahat.
Respons abnormal : respons persisten setelah bulan keempat
dapat menandakan cedera neurologis. Respons menetap tampak
pada cedera SSP dan gangguan neurologis.
8) Terkejut
Respons normal : bayi melakukan abduksi dan fleksi seluruh
ekstremitas dan dapat mulai menangis bila mendapat gerakan
mendadak atau suara keras.
Respons abnormal : tidak adanya respons dapat menandakan
defisit neurologis atau cedera. Tidak adanya respons secara
lengkap dan konsisten terhadap bunyi keras dapat menandakan
ketulian. Respons dapat menjadi tidak ada atau berkurang
selama tidur malam.
9) Ekstensi silang
Respons normal : kaki bayi yang berlawanan akan fleksi dan
kemudian ekstensi dengan cepat seolah-olah berusaha untuk
210
memindahkan stimulus ke kaki yang lain bila diletakkan
telentang bayi akan mengekstensikan satu kaki sebagai respons
terhadap stimulus pada telapak kaki.
Resposn abnormal : respons yang lemah atau tidak ada respons
yang terlihat pada cedera sara perifer atau fraktur tulang
panjang.
10) Glabellar “blink”
Respons normal : bayi akan berkedip bila dilakukan 4 atau 5
ketuk pertama pada batang hidung saat mata terbuka.
Respons abnormal : terus berkedip dan gagal untuk berkedip
menandakan kemungkinan gangguan neurologis.
11) Palmar grasp
Respons normal : jari bayi akan melekuk di sekeliling benda dan
menggenggamnya seketika bila jari diletakkan di tangan bayi.
Respons abnormal : respons ini berkurang pada prematuritas.
Asimetris terjadi pada kerusakan saraf perifer (pleksus brakialis)
atau fraktur humerus. Tidak ada respons yang terjadi pada
defisit neurologis yang berat.
12) Plantar grasp
Respons normal : jari bayi akan melekuk di sekeliling benda
seketika bila jari diletakkan di telapak kaki bayi.
Respons abnormal : respons yang berkurang terjadi pada
prematuritas. Tidak ada respons yang terjadi pada defisit
neurologis yang berat.
13) Tanda babinski
Respons normal : jari-jari kaki bayi akan hiperekstensi dan
terpisah seperti kipas dari dorsofleksi ibu jari kaki bila satu sisi
kaki digosok dari tumit ke atas melintasi bantalan kaki
Respons abnormal : tidak ada respons yang terjadi pada defisit
SSP (Sondakh, 2013).
211
f. Perawatan Segera Setelah Bayi lahir
Sebelum bayi lahir, perlengkapan di kamar bersalin harus
diperiksa apakah sudah siap, apakah semua alat sudah lengkap, dan
apakah tidak ada yang macet. Perlengkapan yang diperlukan di
kamar bersalin, yaitu sebagai berikut:
1) Meja tempat bayi yang lengkap dengan lampu 60 watt
2) Tabung oksigen dengan alat pemberi oksigen pada bayi
3) Untuk menjaga kemungkinan terjadinya asfiksia, perlu
menyediakan alat resusitasi
4) Alat pemotong dan pengikat tali pusat dan obat antiseptik serta
kain kasa steril untuk merawat tali pusat
5) Tanda pengenal bayi yang sama dengan ibu
6) Tempat tidur bayi, pakaian bayi, termometer
7) Lain-lain: kapas, kain kasa, baju steril, dan obat antiseptik yang
akan dipakai oleh dokter, mahasiswa, bidan, dan perawat
sebelum menolong persalinan
Setelah bayi lahir, bayi segera dikeringkan, dibungkus dengan
hadnuk kering, dan diletakkan di dada ibu untuk Imunisasi Menyusui
Dini (IMD).
Penilaian klinis bayi normal segera sesudah lahir bertujuan
untuk mengetahui derajat vitalitas dan mengukur reaksi bayi
terhadap tindakan resusitasi. Derajat vitalitas bayi adalah
kemampuan sejumlah fungsi tubuh yang bersifat esensial dan
kompleks untuk kelangsungan hidup bayi, seperti pernapasan,
denyut jantung, sirkulasi darah, dan refleks primitif (misal:
menghisap dan mencari puting susu). Pada saat kelahiran, apabila
bayi gagal menunjukkan reaksi vital, akan terjadi penurunan denyut
jantung secara cepat, tubuh menjadi biru atau pucat, dan keadaan
umum bayi akan menurun dengan cepat dan mungkin menyebabkan
kematian. Beberapa bayi mungkin pulih secara spontan dalam 10-30
212
menit sesudah lahir, tetapi bayi ini tetap berisiko tinggi mengalami
cacat di masa dewasa.
Pada waktu lahir, bayi sangat aktif. Frekuensi jantung dalam
menit-menit pertama kira-kira 180 kali/menit yang kemudian turun
sampai 140 kali/menit-120 kali/menit pada waktu bayi berusia 30
menit. Pernapasan cepat pada menit-menit pertama (kira-kira 80
kali/menit) disertai dengan pernapasan cuping hidung, retraksi
suprasternal dan interkostal, serta rintihan hanya berlangsung 10-15
menit. Akibat keaktifan yang berlebihan adalah bayi bayi menjadi
tegang dan relatif tidak memberi reaksi terhadap rangsangan dari
luar dan dari dalam. Dalam keadaaan ini, bayi tertidur selama
beberapa menit sampai 4 jam. Pada saat pertama kali bangun dari
tidurnya, ia menjadi mudah terangsang, dengan frekuensi jantung
meningkat dan perubahan warna kulit serta kadang-kadang keluar
lendir dari mulut. Sesudah masa ini dilampaui, keadaan bayi mulai
stabil, daya isap dan refleks mulai teratur.
Evaluasi bayi baru lahir dilaksanakan segera setelah bayi lahir
(menit pertama) dengan menilai dua indikator kesejahteraan bayi,
yaitu pernapasan dan frekuensi jantung bayi. Penilaian ini mengacu
pada Skor Sigtuna ( Tando, 2016).
g. APGAR Score
Pada tahun 1952, seorang ahli anak sekaligus ahli anastesi, Dr.
Virginia Apgar memublikasikan cara evaluasi bayi baru lahir dengan
skor yang disebut nilai APGAR, yang diambil dari nama
belakangnya. Pada tahun 1962, Dr. Joseph Butterfield seorang ahli
anak membuat akronim APGAR, yaitu Appearance (warna kulit),
Pulse (denyut nadi), Grimace (respons refleks), Activity (tonus otot),
dan Resporatory (pernapasan). Evaluasi nilai APGAR dilakukan
mulai dari menit pertama sampai 5 menit. Hasil pengamatan masing-
masing aspek dituliskan dalam skala skor 0-2 (Tando, 2016).
213
Tabel 2.12 Penilaian bayi dengan metode APGAR ASPEK PENGAMATAN
BAYI BARU LAHIR
SKOR
0 1 2
Appearance/warna kulit Seluruh tubuh
bayi berwarna
kebiruan
Warna kulit
tubuh
normal,
tetapi tangan
dan kaki
berwarna
kebiruan
Warna kulit
seluruh tubuh
normal
Pulse/denyut nadi Denyut nadi
tidak ada
Denyut nadi
<100 kali
per menit
Denyut nadi
>100 kali per
menit
Grimace/repsons reflex Tidak ada
respons
terhadap
stimulasi
Wajah
meringis saat
distimulasi
Meringis,
menarik,
batuk, atau
bersin saat
distimulasi
Activity/tonus otot Lemah, tidak
ada gerakan
Lengan dan
kaki dalam
posisi fleksi
dengan
sedikit
gerakan
Bergerak aktif
dan spontan
Respiratory/pernapasan Tidak
bernapas,
pernapasan
lambat atau
tidak teratur
Menangis
lemah,
terdengar
seperti
merintih
Menangis
kuat,
pernapasan
baik dan
teratur
Sumber: Walyani dan Purwoastuti, 2016, Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru
Lahir, bagian evaluasi awal bbl, Yogyakarta, halaman: 142.
Penilaian APGAR 5 menit pertama dilakukan saat kala III
persalinan dengan menempatkan bayi baru lahir di atas perut ibu dan
ditutupi dengan selimut atau handuk kering yang hangat.
Selanjutnya, hasil pengamatan BBL berdasarkan kriteria tersebut
dituliskan dalam tabel skor APGAR (Tando, 2016).
Tabel 2.13 Pengamatan BBL dengan APGAR score
ASPEK PENGAMATAN 5 MENIT
PERTAMA
10 MENIT
PERTAMA
A = Appeatance (warna kulit)
P = Pulse (Denyut nadi/menit)
G = Grimace (respons refleks)
A = Activity (tonus otot)
R = Respiratory (pernapasan
bayi)
JUMLAH SKOR
Sumber: Walyani dan Purwoastuti, 2016, Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir,
bagian evaluasi awal bbl, Yogyakarta, halaman: 142.
214
Hasil dijumlahkan ke bawah untuk menentukan penatalaksanaan
BBL dengan tepat. Hasil penilaian pada menit pertama dan menit
kelima merupakan patokan dalam menentukan penanganan segera
setelah lahir (Walyani dan Purwoastuti, 2016).
Tabel 2.14 Analisis hasil pengamatan BBL berdasarkan APGAR score Nilai APGAR 5 Menit Pertama Penanganan
0-3 - Tempatkan di tempat hangat dengan
lampu sebagai sumber penghangat
- Pemberian oksigen
- Resusitasi
- Stimulasi
- Rujuk
4-6 - Tempatkan di tempat hangat
- Pemberian oksigen
- Stimulasi taktil
7-10 - Dilakukan penatalaksanaan sesuai dengan
penatalaksanaan bayi normal
Sumber: Walyani dan Purwoastuti, 2016. Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir,
bagian evaluasi awal bbl, yogyakarta, halaman: 143.
h. Neonatus Beresiko Tinggi
Menurut Tando (2016) neonatus yang beresiko tinggi, antara
lain sebagai berikut:
1) Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR)
2) Asfiksia neonatorum
3) Sindrom gawat napas
4) Ikterus
5) Perdarahan tali pusat
6) Kejang
7) Hipotermia
8) Hipertermia
9) Hipoglikemia
10) Tetanus neonatorum
11) Penyakit yang diderita ibu selama kehamilan
215
i. Tanda Bahaya Neonatus
Menurut Tando (2016) tanda bahaya pada bayi adalah sebagai
berikut:
1) Sulit menyusu
2) Letargi (tidur terus sehingga tidak menyusu)
3) Demam atau hipotermia
4) Tidak defekasi selama 3 hari (kemungkinan tidak mempunyai
lubang anus)
5) Sianosis pada kulit atau bibir
6) Ikterus berat
7) Muntah terus menerus
8) Muntah dan perut membesar
9) Kesulitan bernapas
10) Perilaku tangis yang tidak normal
11) Mata bengkak dan bernanah/berair
12) Mekonium cair berwarna hijau gelap dengan lendir/darah
j. Kunjungan Neonatus
Menurut Kementrian Kesehatan RI (2019a), kunjungan neonatus
esensial dilakukan sebanyak 3 kali kunjungan, meliputi:
1) 1 kali pada umur 6-48 jam (KN 1)
2) 1 kali pada umur 3-7 hari (KN 2)
3) 1 kali pada umur 8-28 hari (KN 3)
Pelayanan neonatal yang dilakukan meliputi:
1) Menjaga bayi tetap hangat
2) Pemeriksaan neonatus menggunakan Manajemen Terpadu Bayi
Muda (MTBM)
3) Bimbingan pemberian ASI dan memantau kecukupan ASI
4) Perawatan pertumbuhan neonatus
5) Masalah yang paling sering dijumpai pada neonatus
216
k. Imunisasi
1) Pengertian
Imunisasi adalah usaha memberikan kekebalan pada bayi
dan anak dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar
tubuh membuat zat anti untuk pencegahan terhadap penyakit
tertentu. Vaksin adalah bahan yang dipakai untuk merangsang
pembentukan zat anti yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui
suntikkan dan melalui mulut.
Istilah imunisasi dan vaksinasi sering diartikan sama
meskipun arti sebenarnya berbeda. Imunisasi adalah
pemindahan atau transfer antibodi secara pasif, sedangkan
vaksinasi adalah pemberian vaksin (antigen) yang dapat
merangsang pembentukan imunitas (antibodi) dari sistem imun
di dalam tubuh (Muhadir, et al., 2008). Imunisasi tidak cukup
hanya dilakukan satu kali, tetapi harus dilakukan secara bertahap
dan lengkap agar tidak rentan terhadap berbagai penyakit yang
sangat membahayakan kesehatan dan kehidupan anak (Tando,
2016).
2) Manfaat imunisasi
a) Untuk anak
Mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit,
kemungkinan cacat, dan kematian
b) Untuk keluarga
(1) Menghilangkan kecemasan dan faktor psikologis
pengobatan jika anak sakit
(2) Mendorong pembentukan keluarga apabila orang tua
yakin bahwa anak akan menjalani masa kanak-kanak
yang nyaman
c) Untuk negara
(1) Memperbaiki tingkat kesehatan
217
(2) Menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk
melanjutkan pembangunan negara (Tando, 2016).
3) Tujuan imunisasi
a) Mencegah penyakit tertentu pada seseorang
b) Menghilangkan penyakit tertentu pada sekelompok
masyarakat (populasi)
c) Menghilangkan penyakit tertentu dari dunia (Tando, 2016).
4) Jenis imunisasi
Imunisasi ada dua jenis yaitu :
a) Imunisasi pasif, merupakan kekebalan bawaaan dari ibu
terhadap penyakit
b) Imunisasi aktif, merupakan kekebalan yang didapat dari
pemberian bibir penyakit lemah yang mudah dikalahkan
oleh kekebalan tubuh biasa guna membentuk antibodi
terhadap penyakit yang sama, baik yang lemah maupun
yang kuat (Tando, 2016).
5) Tempat pelayanan imunisasi
a) Pos pelayanan terpadu (Posyandu)
b) Puskesmas, rumah sakit bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan
Anak (BKIA), atau rumah sakit pemerintah
c) Klinik praktik bidan/dokter atau rumah sakit swasta
(Tando, 2016).
6) Imunisasi Dasar
Imunisasi dasar diberikan untuk mendapatkan kekebalan secara
aktif. Imunisasi yang diwajibkan sesuai program pengembangan
imunisasi (PPI) adalah sebagai berikut:
a) Vaksin Bacillus Calmette-Guerin (BCG)
Vaksin BCG merupakan vaksin hidup sehingga tidak
diberikan kepada pasien dengan gangguan imun jangka
panjang 9leukimia, pengobatan steroid jangka panjang,
HIV). Tujuan imunisasi BCG bukan untuk mencegah tBc,
218
melainkan untuk mengurangi risiko TBC berat, seperti TBC
meningitis dan TBC milier. Imunisasi ini diberikan kepada
bayi yang berusia 2 bulan atau kurang. Imunisasi ini
diberikan kepada anak dengan uji Mantoux negatif. Dosis
untuk bayi (usia kurang dari 1 tahun) adalah 0,05 ml dan
anak 0,10 ml. vaksin ini diberikan melalui suntikan
intrakutan di daerah insersi muskulus deltoideus kanan
(lengan atas kanan). Tempat ini dipilih dengan alasan lemak
subkutis tebal, ulkus yang terbentuk tidak mengganggu
struktur otot setempat dan sebagai tanda baku untuk
keperluan diagnosis jika dibutuhkan (Tando, 20160.
b) Vaksin Polio/Oral Polio Vaccine (OPV)
Vaksin virus polio hidup oral berisi virus polio tipe 1,
2,3 yang masih hidup, tetapi sudah dilemahkn. Vaksin ini
digunakan secara rutin sejak bayi lahir sebagai dosis awal
dengan 2 tetes (0,1 ml). vaksin virus polio hidup oral adalah
vaksin polio trivalen yang terdiri atas suspensi virus
poliomielitis tipe 1, 2, dan 3 (strain sabin) yang sudah
dilemahkan, dibuat dalam biakan jaringan ginjal kera dan
distabilkan dengan sukrosa. Apabila vaksin yang diberikan
dimuntahkan dalam 10 menit, harus diberikan dosis
pemberian ulang (Tando, 2016).
c) Vaksin Hepatitis B Prefilled Injection Device (PID)
Vaksin hepatitis B PID adalah vaksin rekombinan
yang telah diinaktivasikan dan bersifat non-infeksi, berasal
dari HbsAg yang dihasilkan dalam sel ragi (Hansenula
polynorpha) menggunakan teknologi DNA rekombinan.
Vaksin diberikan melalui IM dalam. Pada neonatus dan
bayi, penyuntikan vaksin ini dilakukan di anterolateral paha,
sedangkan pada anak dan orang dewasa dilakukan di regio
deltoid. Imunisasi Hepatitis B-1 diberikan sedini mungkin
219
setelah lahir untuk memutuskan rantai transmisi material
ibu dan bayi. Pemberian vaksin hepatitis B diberikan
sebanyak 1 dosis dengan penyuntikkan secara IM pada
anterolateral paha dan diberikan pada usia 0-7 hari
d) Vaksin Difteria-Pertusis-Tetanus (DPT)
Vaksin DPT terdiri atas vaksin berikut ini:
(1) Vaksin toksoid difteria
Vaksin ini merupakan bagian dari vaksin DPT atau
Diptheria Toxoid (DT). Difteria disebabkan oleh
bakteri yang memproduksi racun. Vaksin terbuat dari
toksoid, yaitu racun difteria yang telah dilemahkan.
Vaksin difteria akan rusak jika dibekukan dan jika
terkena panas.
(2) Vaksin pertusis
Vaksin ini merupakan bagian dari vaksin DPT.
Penyebab penyakit pertusis adalah bakteri. Vaksin
terbuat dari bakteri yang telah dimatikan. Vaksin
pertusis mudah rusak jika terkena panas. Sama seperti
vaksin BCG, dalam vaksin DPT, komponen pertusis
merupakan vaksin yang paling mudah rusak.
(3) Vaksin tetanus
Vaksin ini merupakan bagian dari vaksin DPT, DT,
atau sebagai Toksoid Tetanus (TT). Tetanus disebabkan
oleh bakteri yang memproduksi toksin. Vaksin terbuat
dari toksin tetanus yang telah dilemahkan. Toksoid
tetanus akan rusak jika dibekukan dan jika terkena
panas. Pemberian vaksin DPT melalui intramuskular
(IM) 0,5 ml sebanyak 3 dosis. Dosis pertama pada usia
2 bulan dan dosis selanjutnya dengan interval minimal
4 minggu (1 bulan) (Tando, 2016).
220
e) Vaksin Campak
Vaksin campak merupakan vaksin virus hidup yang
dilemahkan. Setiap dosis (0,5 ml) mengandung tidak kurang
1.000 infective unit virus strain CAM 70 dan tidak lebih dari
100 mcg residu kanamisin dan 30 mcg residu eritromisin.
Vaksin campak diberikan dalam satu dosis 0,5 ml melalui
suntikan subkutan dalam pada usia 9 bulan. Imunisasi ulang
perlu diberikan saat anak berusia 5-6 tahun untuk
mempertinggi serokonversi. Apabila anak yang berusia 15-
18 bulan telah mendapatkan imunisasi Measles, Mumps,
and Rubella (MMR), imunisasi ulang campak pada usia 5
tahun tidak perlu diberikan lagi (Tando, 2016).
Tabel 2.15 Jadwal imunisasi Usia Jenis imunisasi
0 bulan Polio 1,BCG, HB 0
2 bulan Polio 2, DPT, HB 1
3 bulan Polio 3, DPT, HB 2
4 bulan Polio 4, DPT, HB 3
9 bulan Campak
Sumber: Tando, 2016, Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi & Anak Balita, Bagian
Imunisasi Dasar, Jakarta, Halaman 156.
2. Konsep Dasar Asuhan Kebidanan Neonatus
a. Pengkajian Data
Menurut Walyani dan Purwoastuti (2015), melakukan pengkajian
dengan mengupulkan seua data yang dibutuhkan untuk engevaluasi
keadaan bayi baru lahir.
1) Pengkajian setelah lahir
Pengkajian ini bertujuan untuk mengkaji adaptasi bayi baru lahir
dari kehidupan dala uterus ke kehidupan luar uterus yaitu
dengan penilaian APGAR, meliputi:
221
Tabel 2.12 Penilaian Bayi dengan APGAR Score
Aspek Pengamatan
Bayi Baru Lahir
SKOR
0 1 2
Appearance
(warna kulit)
Seluruh tubuh bayi
berwarna kebiruan
Warna kulit tubuh
normal, tetapi
tangan dn kaki
berwarna kebiruan
Warna kulit
seluruh tubuh
normal
Pulse
(nadi)
Denyut jantung
tidak ada
Denyut jantung
<100 kali per
menit
Denyut jantung
>100 per menit
Grimace(respon
reflek)
Tidak ada respon
terhadap stimulasi
Wajah meringis
saat distimulasi
Meringis,
menarik, batuk
atau bersin saat
stimulasi
Activity
(tonus otot)
Lemah, tidak ada
gerakan
Lengan dan kaki
dalam posisi fleksi
dengan sedikit
gerakan
Bergerak aktif
dan spontan
Respiratory
(pernafasan)
Tidak bernapas,
pernapasan lambat
dan tidak teratur
Menangis lemah,
terdengar seperti
merintih
Menangis kuat,
pernapasan baik
dan teratur
Sumber: Walyani dan Purwoastuti. 2016. Asuhan kebidanan Persalinan dan Bayi Baru
Lahir
Hasil nilai APGAR score setiap variabel dinilai dengan
angka 0, 1 dan 2, milai tertinggi adalah 10, selanjutnya dapat
ditentukan keadaan bayi sebagai berikut:
a) Nilai 7-10 enunjukkan bahwa bayi dala keadaan baik
(vigrous baby)
b) Nilai 4-6 menunjukkan bayi mengalami depresi sedang dan
mebutuhkan tindakan resusitasi.
c) Nilai 0-3 menunjukkan bayi mengalami depresi serius dan
membutuhkan resusitasi segera sampai ventilasi(Walyani dan
Purwoastuti, 2016).
2) Pengkajian keadaan fisik
Data subyektif bayi baru lahir yang harus dikumpulkan, antara
lain riwayat kesehatan bayi baru lahir yang penting dan harus
dikaji adalah:
a) Faktor genetik
b) Faktor aternal (ibu)
c) Faktor antenatal
222
d) Faktor perinatal
Data obyektif bayi baru lahir yang harus dikumpulkan antara
lain:
a) Pemeriksaan umum
Pengukuran antropometri yaitu pengukuran lingkar kepala
yang dala keadaan normal berkisar 33-35 cm, lingkar dada
30,5-33 cm, panjang badan 45-50 cm, berat badan bayi
2500-4000 gram.
b) Pemeriksaan tanda-tanda vital
Suhu tubuh, nadi, pernafasan bayi baru lahir bervariasi
dalam berespon terhadap lingkungan.
(1) Suhu bayi
Suhu bayi dalam keadaan normal berkisar antara 36,5-
37,50C pada pengukuran di axila.
(2) Nadi
Denyut nadi bayi yang normal berkisar 120-140 kali
permenit.
(3) Pernafasan
Pernafasan pada bayi baru lahir tidak teratur
kedalaannya, kecepatannya, iraanya. Pernafasannya
bervariasi dari 30 sampai 60 kali permenit.
(4) Tekanan darah
Tekanan darah bayi baru lahir rendah dan sulit untuk di
ukur secara akurat. Rata-rata tekanan darah pada waktu
lahir adalah 80/64 mmHg.
c) Pemeriksaan fisik secara sistematis (head to toe)
Pemeriksaan fisik secara sistematis pada bayi baru lahir di
ulai dari:
(a) Kepala
Raba sepanjang garis sutura dan fontanel, apakah
ukuran dan tampilannya normal. Sutura yang berjarak
223
lebar mengidentifikasikan yang preterm, moulding
yang buruk atau hidrosefalus. Pada kelahiran spontan
letak kepala, sering terlihat tulang kepala tumpang
tindih yang disebut moulding atau moulase. Fontanel
anterior harus diraba, fontanel yang besar dapat terjadi
akibat prematuritas atau hidrosefalus, sedangkan yang
terlalu kecil terjadi pada mikrosefali. Jika fontanel
menonjol, hal ini diakibatkan peningkatan tekanan
intrakranial, sedangkan yang cekung dapat terjadi
akibat dehidrasi.
Periksa adanya trauma kelahiran misalnya: caput
suksedaneum, sefalheatoma, perdarahan
subaponeurotik atau fraktur tulang tengkorak.
Perhatikan adanya kelainan congenital seperti:
anensefali, mikrosefali, kraniotabes dan sebagainya.
(b) Telinga
Periksa dan pastikan jumlah, bentuk dan posisinya
pada bayi cukup bulan, tulang rawan sudah matang.
Daun telinga harus berbentuk sempurna dengan
lengkungan yang jelas dibagian atas. Perhatikan letak
daun telinga. Daun telinga yang letaknya rendah (low
set ears) terdapat pada bayi yang mengalami sindrom
tertentu (pierrerobin). Perhatikan adanya kulit
tambahan atau aurikel hal ini dapat berhubungan
dengan abnormalitas ginjal.
(c) Mata
Periksa adanya strabismus yaitu koordinasi mata
yang belum sempurna. Periksa adanya glaucoma
congenital, mulanya akan nampak sebagai pembesaran
kemudian sebagai kekerruhan pada kornea. Katarak
congenital akan mudah terlihat yaitu pupil berwarna
224
putih. Pupil harus tampak bulat. Terkadang ditemukan
bentuk seperti lubang kunci (kolobama) yang dapat
mengindikasikan adanya defek retina.
Periksa adanya trauma seperti palpebra, perdarahan
konjungtiva atau retina, adanya secret pada mata,
konjungtivitis oleh kuman gonokokus dapat menjadi
panofralmiadan menyebabkan kebutaan. Apabila
ditemukan epichantus melebar kemungkinan bayi
mengalami sindrom down.
(d) Hidung atau Mulut
Bibir bayi baru lahir harus kemerahan dan lidahnya
harus rata dan simetris. Bibir dipastikan tidak adanya
sumbing dan langit-langit harus tertutup. Reflek hisap
bayi harus bagus, dan berespon terhadap rangsangan.
Kaji bentuk dan lebar hidung, pada bayi cukup bulan
lebarnya harus lebih 2,5 cm.
Bayi harus bernafas dengan hidung, jika melalui
mulut harus diperhatikan kemungkinan adanya
obstruksi jalan nafas karena atresia koana bilateral,
fraktur tulang hidung atau ensefalokel yang menonjol
ke nasofaring.
(e) Leher
Ukuran leher normalnya pendek dengan banyak
lipatan tebal. Leher berselaput berhubungan dengan
abnormalitas kromosom. Periksa kesimetrisannya.
Pergerakan harus baik. Jika terdapat keterbatasan
pergerakan kemungkinan ada kelainan tulang leher.
Periksa adanya trauma leher yang dapat menyebabkan
kerusakan pada fleksus brakhialis. Lakukan perabaan
untuk mengidentifikasi adanya pembengkakan.
225
Periksa adanya pembesaran kelenjar tiroid dan
vena jugularis. Adanya lipatan kulit yang berlebihan
dibagian belakang leher menunjukkan adanya
kemungkinan trisomy.
(f) Dada
Kontur dan simetrisitas dada normalnya adalah
bulat dan simetris. Payudara baik pada laki-laki
maupun perempuan terlihat membesar karena pengaruh
hormone wanita dari darah ibu. Periksa kesimetrisan
gerakan dada saat bernafas. Apabila tidak simetris
kemungkinan bayi mengalami pneumotorik, paresis
diafragma atau hernia diafragatika. Pernafasan yang
normal dinding dada dan abdomen bergerak secara
bersamaan. Tarikan sternum atau interkostal pada saat
bernafas perlu diperhatikan.
(g) Bahu, Lengan dan Tangan
Gerakan normal, kedua lengan harus bebas gerak,
jika gerakan kurang kemungkinan adanya kerusakan
neurologis atau fraktur. Periksa jumlah jari. Perhatikan
adanya plidaktil atau sindaktil. Telapak tangan harus
dapat terbuka, garis tangan yang hanya satu buah
berkaitan dengan abnormalitas kromosom, seperti
trisomi 21. Periksa adanya paronisia pada kuku yang
dapat terinfeksi atau tercabut sehingga menimbulkan
luka dan perdarahan.
(h) Perut
Bentuk, penonjolan sekitar tali pusat pada saat
menangis, perdarahan tali pusat. Perut harus tampak
bulat dan bergerak secara bersamaan dengan gerakan
dada saat bernafas. Kaji adanya pembengkakan, jika
perut sangat cekung kemungkinan terdapat hernia
226
diafragmatika, perut yang membuncit keungkinan
karena hematosplenomegali atau tumor lainnya. Jika
perut kembung kemungkinan adanya enterokolitis
vesikalis, omfalokel atau duktus omfaloentriskus
persisten.
(i) Kelamin
Pada wanita labia mayora dapat ditemukan adanya
verniks dan smegma (kelenjar kecil yang terletak
dibawah prepusium mensekresi bahan yang seperti
keju) pada lekukan. Labia mayora normalnya menutupi
labia minora dan klitoris. Klitoris normalnya menonjol.
Menstruasi palsu kadang ditemukan, diduga pengaruh
hormon ibu disebut juga psedomenstruasi, normalnya
terdapat umbai hymen. Pada bayi laki-laki rugae
normalnya tampak pada skrotum dan kedua testis turun
kedalam skrotum. Meatus urinarius normalnya terletak
pada ujung glands penis. Epispadia adalah istilah yang
digunakan untuk menjelaskan kondisi meatus berada
dipermukaan dorsal. Hipospadia untuk menjelaskan
kondisi meatus berada dipermukaan ventral penis.
(j) Ekstermitas Atas dan Bawah
Ekstermitas bagian atas normalnya fleksi dengan
baik dengan gerakan yang simetris. Reflek
menggenggam normalnya ada. Kelemahan otot parsial
atau komlet dapat menandakan trauma pada pleksus
brankhialis. Nadi brankhialis normalnya ada.
Ekstermitas bagian bawah normalnya pendek, bengkok
dan fleksi dengan baik. Nadi femoralis dan pedis
normalnya ada.
227
(k) Punggung
Periksa spina dengan cara menelungkupkan bayi,
cari adanya tanda-tanda abnormalitas seperti spina
bifida, pembengkakan atau cekungan, lesung atau
bercak kecil berambut yang dapat menunjukkan adanya
abnormalitas medulla spinalis atau kolumna vertebrata.
(l) Kulit
Verniks (tidak perlu dibersihkan karena untuk
menjaga kehangatan tubuh bayi), warna,
pembengkakan atau bercak-bercak hitam, tanda-tanda
lahir. Perhatikan adanya lanugo, jumlah yang banyak
terdapat pada bayi kurang bulan.
(m) Refleks
Refleks berkedip, batuk, bersin, dan muntah ada
pada waktu lahir dan tetap tidak berubah sampai
dewasa. Beberapa refleks lain normalnya ada pada
waktu lahir, yang menunjukkan imaturitas neurologis,
refleks-refleks tersebut akan hilang pada tahun pertama.
Tidak adanya refleks-refleks ini menandakan masalah
neurologis yang serius.
b. Merencanakan Diagnosa
Mengidentifikasi diagnosis atau masalah potensial yang mungkin
akan terjadi berdasarkan Diagnosis atau masalah yang sudah
diidentifikasi (Walyani dan Purwoastuti, 2016).
Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter
dan/atau ada hal yang perlu dikonsultasi atau ditangani bersama
dengan anggota tim kesehatan lain sesuai kondisi bayi (Walyani dan
Purwoastuti, 2016).
c. Merencanakan asuhan kebidanan
Merencanakan asuhan menyeluruh yang rasional sesuai dengan
temuan pada langkah sebelumnya (Walyani dan Purwoastuti, 2016).
228
d. Melaksanakan asuhan kebidanan
Mengarahkan atau melaksanakan rencana asuhan secara efektif dan
aman (Walyani dan Purwoastuti, 2016)
e. Evaluasi
Mengevaluasi kefektifan asuhan yang sudah diberikan (Walyani dan
Purwoastuti, 2016).
f. Dokumentasi SOAP
Model dokumentasi yang digunakan dalam asuhan kebidanan
yaitu dalam bentuk catatan perkembangan karena bentuk asuhan
yang diberikan berkesinambungan dan menggunakan proses yang
terus menerus dengan menggunakan subjektif, objektif, analisis, dan
penatalaksanaan (SOAP) yang merupakan salah satu metode
pendokumentasian.
1) S = Subjektif
Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data
klien melalui anamnesis antara lain tanggal, tahun, waktu,
biodata, riwayat, termasuk kondisi klien. Catatan data spesifik
atau fokus. Tanda dan gejala subjektif yang didapatkan dari
hasil bertanya pada klien, suami dan keluarga. Catatan ini
berhubungan dengan masalah sudut pandang klien. Ekspresi
klien mengenai kekhawatiran dan keluhannya dicatat sebagai
kutipan langsung atau ringkasan yang berhubungan dengan
diagnosa.
2) O = Objektif
Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data
klien melalui pengamatan dan terukur, pemeriksaan fisik klien
didapatkan melalui inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi,
termasuk data penunjang. Data ini memberikan bukti gejala
klinis klien dan fakta yang berhubungan dengan diagnosa.
229
3) A = Analisis
Menggambarkan pendokumentasian hasil analisis, diagnosis,
dan masalah kebidanan.
4) P = Penatalaksanaan
Mencatat seluruh perencanaan dan penatalaksanaan yang telah
dilakukan, misalnya tindakan antisipatif, tindakan segera,
tindakan secara komprehensif, penyuluhan, dukungan,
kolaborasi, evaluasi/follow up dan rujukan. Dokumentasi
menunjukkan perencanaan yang tepat (Astuti dkk, 2017).
E. Keluarga Berencana Pascasalin
1. Konsep Dasar KB
a. Pengertian
Keluarga berencana merupakan usaha menjarangkan atau
merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan menggunakan
kontrasepsi (Sulistyawati, 2013).
Keluarga berencana pasca salin adalah melakukan tindakan KB
ketika wanita baru melahirkan dan gugur kandungan di rumah sakit,
atau memberi pengarahan agar memilih KB efektif (melakukan
sterilisasi wanita atau pria, menggunakan AKDR, menerima KB
hormonal dalam bentuk suntik atau susuk (Prawirohardjo, 2014).
Kontrasepsi yaitu pencegahan terbuahinya sel telur oleh sel sperma
(konsepsi) atau pencegahan menempelnya sel telur yang telah
dibuahi ke dinding rahim. Kontrasepsi pasca persalinan merupakan
inisiasi pemakaian metode kontrasepsi dalam waktu 6 minggu
pertama pascapersalinan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang
tidak diinginkan, khususnya pada 1-2 tahun pertama pascapersalinan
(Mulyani dan Rinawati, 2013).
b. Pentingnya KB Pascasalin
b. Mengatur jarak dan mencegah kehamilan agar tidak terlalu rapat
(minimal 2 tahun setelah melahirkan)
230
c. Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan
d. Menjaga dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita
e. Ibu memiliki waktu dan perhatian yang cukup untuk dirinya
sendiri, anak dan keluarga (Kemenkes RI, 2016).
c. Macam-Macam KB Pascasalin
1) Metode Amenorrhea Laktasi (MAL)
a) Pengertian
Metode Amenorrhea Laktasi (MAL) adalah kontrasepsi
yang mengandalkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara
ekslusif, artinya ASI hanya diberikan kepada bayinya tanpa
makanan atau minuman tambahan hingga usia 6 bulan
(Mulyani dan Rinawati, 2013).
b) Cara Kerja
Penundaan atau penekanan ovulasi (Mulyani dan Rinawati,
2013).
c) Keuntungan Kontrasepsi
(1) Efektifitas tinggi (tingkat keberhasilan 98% pada 6
bulan pascapersalinan)
(2) Tidak mengganggu saat berhubungan seksual
(3) Segera efektif bila digunakan secara benar
(4) Tidak ada efek samping secara benar
(5) Tidak perlu pengawasan medis
(6) Tidak perlu obat atau alat
(7) Tanpa biaya (Mulyani dan Rinawati, 2013).
d) Keuntungan Nonkontrasepsi
(1) Untuk bayi
(a) Mendapatkan kekebalan pasif (mendapat dukungan
antibodi melalui ASI)
(b) Merupakan asupan gizi yang terbaik dan sempurna
untuk tumbuhkembang bayi yang optimal
231
(c) Bayi terhindar dari keterpaparan terhadap
kontaminasi dari air, susu lain atau formula, atau
alat minum yang dipakai.
(2) Untuk ibu
(a) Dapat mengurangi perdarahan pascapersalinan
(b) Dapat mengurangi risiko anemia
(c) Dapat meningkatkan kasih sayang antara ibu dan
bayi (Mulyani dan Rinawati, 2013).
e) Kelemahan metode MAL
(1) Perlu persiapan dan perawatan sejak awal kehamilan
agar segera menyusui dalam 30 menit pascapersalinan
(2) Sulit dilaksanakan karena kondisi sosial
(3) Efektifitas tinggi hanya sampai kembalinya haid atau
sampai dengan 6 bulan
(4) Tidak melindungi terhadap IMS termasuk HIV/AIDS
dan virus Hepatitis b/HBV (Mulyani dan Rinawati,
2013).
f) Ibu yang dapat menggunakan MAL
(1) Ibu menyusui secara penuh (full breast feeding) dan
lebih efektif bila pemberian ≥ 8x sehari
(2) Ibu yang belum haid sejak pascapersalinan
(3) Umur bayi kurang dari 6 bulan
(4) Harus dilanjutkan dengan pemakaian metode
kontrasepsi lainnya bila ibu sudah mendapatkan
menstruasi (Mulyani dan Rinawati, 2013).
g) Ibu yang seharusnya tidak memakai MAL
(1) Sudah mendapat haid setelah melahirkan
(2) Tidak menyusui bayinya secara eksklusif
(3) Usia bayi sudah lebih dari 6 bulan
232
(4) Bekerja dan terpisah dari bayinya lebih dari 6 jam serta
tidak memberikan ASI perah (Mulyani dan Rinawati,
2013).
h) Hal-hal yang perlu diketahui oleh ibu yang menggunakan
metode MAL
(1) Bayi disusui secara on demand (menurut kebutuhan
bayi)
(2) Waktu antara 2 pengosongan payudara tidak lebih dari
4 jam
(3) Ibu tetap memberikan ASInya pada malam hari karena
menyusui pada malam hari membantu mempertahankan
kecukupan persediaan ASI
(4) Biarkan bayi menghisap sampai bayi sendiri yang
melepaskannya
(5) Ketika ibu mulai haid lagi, itu pertanda ibu sudah subur
kembali dan harus segera menggunakan metode KB
lainnya.
(6) Jika suami atau pasangan berisiko tinggi terpapar
infeksi menular seksual (IMS), termasuk AIDS maka
harus pakai kondom ketika memakai metode MAL
(Mulyani dan Rinawati, 2013).
2) Kondom
a) Pengertian
Kondom merupakan selubung atau sarung karet yang
terbuat dari berbagai bahan diantaranya karet (lateks),
plastik (vinil) atau bahan alami (produksi hewani) yang
dipasang pada penis untu menampung sperma ketika
seorang pria mencapai ejakulasi saat berhubungan seksual.
Kondom terbuat dari karet sintetis tipis, berbentuk silinder
dengan muaranya berpinggir tebal yang digulung berbentuk
233
rata. Standar kondom dilihat dari ketebalannya, yaitu 0,02
mm (Mulyani dan Rinawati, 2013).
b) Jenis kondom
(1) Kondom dengan aroma dan rasa, kondom ini memiliki
aroma sehingga merangsang pengguna
(2) Kondom berulir (ribbed condom), jenis satu ini
memiliki keunikan di bentuknya yang berulir untuk
menambah kenikmatan pengguna
(3) Kondom ekstra tipis (extra thin), tipe satu ini berbahan
karet dengan ukuran yang sangat tipis sehingga
pengguna dalam bercinta seakan-akan tanpa
menggunakan kondom
(4) Kondom bintik (dotted condom), tipe ini dengan bintik-
bintik di sekitarnya yang bisa menimbulkan efek
mengejutkan bagi wanita
(5) Kondom wanita, kondom yang juga berbahan lateks
atau poliuretan, sehingga elastis dan fleksibel.
(6) Kondom getar, kondom ini dilengkapi dengan cincin
getar di bagian ujungnya. Kondom yang menggunakan
baterai khusus untuk menggerakan cincin getarnya ini
bisa bertahan hingga 30 menit
(7) Kondom baggy, tipe ini bentuknya agak membesar di
bagian ujung serta memiliki ulir di bagian badannya
(8) Kondom biasa (Mulyani dan Rinawati, 2013).
c) Cara kerja
Alat kontrasepsi kondom mempunyai cara kerja sebagai
berikut:
(1) Dapat mencegah sperma masuk ke saluran reproduksi
wanita
(2) Sebagai alat kontrasepsi
234
(3) Sebagai pelindung terhadap infeksi atau tranmisi mikro
organisme penyebab PMS (Mulyani dan Rinawati,
2013).
d) Efektifitas
Pemakaian kondom efektif bila dipakai secara benar setiap
kali berhubungan seksual. Pemakaian kondom yang tidak
konsisten membuat tidak efektif. Angka kegagalan
kontrasepsi kondom sangat sedikit yaitu 2-12 kehamilan per
100 perempuan per tahun (Mulyani dan Rinawati, 2013).
e) Manfaat kondom secara kontrasepsi
(1) Merupakan metode kontrasepsi sementara
(2) Efektif bila pemakaian benar
(3) Tidak mengganggu produksi ASI pada ibu menyusui
(4) Tidak mengganggu kesehatan
(5) Tidak mempunyai pengaruh sistemik
(6) Murah dan tersedia di berbagai tempat
(7) Tidak memerlukan resep dan pemeriksaan khusus
(Mulyani dan Rinawati, 2013).
f) Manfaat kondom secara non kontrasepsi
(1) Adanya peran serta suami untuk ber-KB
(2) Dapat mencegah penularan Penyakit Menular Seksual
(PMS)
(3) Mengurangi insiden kanker serviks
(4) Adanya interaksi sesama pasangan
(5) Mencegah imuno infertilitas (Mulyani dan Rinawati,
2013).
g) Keterbatasan kondom
(1) Efektifitas tidak terlalu tinggi karena bergantung pada
pemakaian kondom yang benar
(2) Tumpahan atau bocoran sperma dapat terjadi jika
kondom disimpan atau dilepaskan secara tidak benar
235
(3) Adanya pengurangan sensitifitas pada penis, sehingga
bisa sedikit mengurangi kenikmatan saat hubungan
seksual
(4) Harus selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual
(5) Perasaan malu membeli di tempat umum
(6) Masalah pembuangan kondom bekas pakai (Mulyani
dan Rinawati, 2013).
Tabel 2.16 Kondisi yang perlu dipertimbangkan bagi pengguna kontrasepsi
kondom Kondom
Baik digunakan Tidak baik digunakan
Ingin berpartisipasi dalam program KB Mempunyai pasangan yang berisiko
tinggi apabila terjadi kehamilan
Ingin segera mendapatkan kontrasepsi Alergi terhadap bahan dasar kondom
Ingin kontrasepsi sementara Menginginkan kontrasepsi jangka panjang
Ingin kontrasepsi tambahan Tidak mau terganggu dalam persiapan
untuk melakukan hubungan seksual
Hanya ingin menggunakan alat
kontrasepsi saat berhubungan
Tidak peduli dengan berbagai persyaratan
kontrasepsi
Berisiko tinggi tertular atau menularkan
PMS
Sumber: Mulyani dan Rinawati, 2013,Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi, Bagian
Metode Barier, Yogyakarta, Halaman 61.
3) Spermisida
a) Pengertian
Spermisida merupakan sediaan kimia (biasanya non
oksinol-9) yang dapat mengubah sperma. Tersedia dalam
bentuk busa vagina, krim, gel dan supposutoria. Spermisida
ditempatkan di vagina sebelum berhubungan seksual.
Kntrasepsi ini juga menyediakan barier fisik ke sperma.
Tidak ada sediaan yang lebih efektif dibanding yang lain.
Spermisida paling baik digunakan dengan kontrasepsi barier
seperti kondom dan diafragma (Mulyani dan Rinawati,
2013).
236
b) Efektifitas spermisida
Hanya sedikit informasi tersedia mengenai efektifitas
spermisida pada pemakaian tunggal. Spermisida dipercayai
hanya memiliki efektifitas sedang. Hal ini menjelaskan
mengapa spermisida dianjurkan dipakai bersama bentuk
kontrasepsi lain (Subekti, 2013).
c) Cara kerja
Menyebabkan sel membran sperma terpecah,
memperlambat pergerakan sperma dan menurunkan
kemampuan pembuahan sel telur (Mulyani dan Rinawati,
2013).
d) Macam-macam spermisida
(1) Busa (Aerosol) efektif segera setelah insersi
(2) Busa spermisida dianjurkan digunakan hanya sebagai
metode kontrasepsi
(3) Tablet vagina, supposutoria, dan film penggunaannya
disarankan menunggu 10-15 menit sesudah dimasukkan
sebelum hubunga seksual
(4) Jenis spermisida jelli biasanya hanya digunakan dengan
diafragma (Mulyani dan Rinawati, 2013).
e) Manfaat kontrasepsi
(1) Efektifitas seketika (busa dan krim)
(2) Tidak mengganggu produksi ASI
(3) Bisa digunakan sebagai pendukung metode lain
(4) Tidak mengganggu kesehatan klien
(5) Tidak mempunyai pengaruh sistemik
(6) Mudah digunakan
(7) Meningkatkan lubrikasi selama hubungan seksual
(8) Tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan kesehatan
khusus (Mulyani dan Rinawati, 2013).
237
f) Manfaat nonkontrasepsi
Merupakan salah satu perlindungan terhadap IMS termasuk
HBV dan HIV/AIDS (Mulyani dan Rinawati, 2013).
g) Keterbatasan
(1) Efektifitas kurang (18-29 kehamilan per 100
perempuan per tahun pertama)
(2) Efektifitas sebagai kontrasepsi bergantung pada
kepatuhan mengikuti cara pengunaan
(3) Ketergantungan pengguna dari motivasi berkelanjutan
dengan memakai setiap melakukan hubungan seksual
(4) Pengguna harus menunggu 10-15 menit setelah aplikasi
sebelum melakukan hubungan seksual (tablet busa
vagina, suppositoria dan krim)
(5) Efektivitas aplikais hanya 1-2 jam (Mulyani dan
Rinawati, 2013).
h) Indikasi spermisida
(1) Pasien yang tidak dianjurkan untuk menggunakan
metode kontrasepsi hormonal
(2) Tidak perokok
(3) Umur pasien tidak lebih dari 35 tahun
(4) Tidak menyukai penggunaan AKDR
(5) Menyusui dan perlu kontrasepsi
(6) Memerlukan proteksi terhadap IMS
(7) Memerlukan metode sederhana sambil menentukan
untuk menggunakan metode yang lain (Mulyani dan
Rinawati, 2013).
i) Kontraindikasi spermisida
(1) Berdasarkan umur dan paritas serta masalah kesehatan
menyebabkan kehamilan menjadi berisiko tinggi
(2) Terinfeksi saluran uretra
238
(3) Tidak stabil secara psikis atau tidak suka menyentuh
alat kelaminnya (vulva dan vagina)
(4) Mempunyai riwayat sindorm syok karena keracunan
(5) Ingin metode KB efektif (Mulyani dan Rinawati, 2013).
j) Cara penggunaan
(1) Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum
mengisi aplikator (busa atau krim) dan insersi
spermisida
(2) Penting untuk menggunakan spermisida setiap
melakukan aktivitas hubungan seksual
(3) Jarak tunggu sesudah memasukkan tablet vagina atau
suppositoria adalah 10-15 menit
(4) Penting untuk mengikuti anjuran dari pabrik tentang
cara penggunaan dan penyimpanan dari setiap produk
(5) Spermisida ditempatkan jauh di dalam vagina sehingga
serviks terlindungi dengan baik (Mulyani dan Rinawati,
2013).
Tabel 2.17 Penanganan efek samping spermisida Efek Samping dan Masalah Penanganan
Iritasi vagina Periksa adanya vaginitis dan IMS. Jika
penyebabnya spermisida, alihkan ke spermisida
lainnya dengan kompoisis kimia berbeda atau bantu
klien memilih metode lain.
Iritasi penis dan tidak nyaman Periksa IMS, jika penyebabnya spermisida, alihkan
ke spermisida lainnya dengan komposisi kimia
berbeda atau bantu klien memilih metode lain
Gangguan rasa panas di vagina Periksa reaksi alergi atau terbakar. Yakinkan bahwa
rasa hangat adalah normal. Jika tidak ada
perubahan, alihkan ke spermisida lainnya dengan
komposisi kimia berbeda atau bantu klien memilih
metode lain
Sumber: Mulyani dan Rinawati, 2013, Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi, Bagian
Metode Barier, Yogyakarta, Halaman 72.
239
4) Diafragma
a) Pengertian
Diafragma adalah kap berbentuk bulat cembung, terbuat
dari karet (lateks) yang diinsersikan ke dalam vagina
sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks
(Mulyani dan Rinawati, 2013).
b) Efektifitas diafragma
Pada pemakaian yang saksama dan konsisten, diafragma
92-96% efektif jika digunakan bersama spermisida untuk
mencegah kehamilan pada tahun pertama. Pada saat wanita
tidak memakai metode ini dengan seksama efektifitasnya
82-90% jika digunakan bersama spermisida untuk
mencegah kehamilan pada tahun pertama. Angka kegagalan
diafragma bergantung pada seberapa efektif wanita
memakainya (Subekti, 2013).
c) Jenis
Ada beberapa jenis diafragma, antara lain yaitu:
(1) Flat spring (flat metal band)
(2) Coil spring (coil wire)
(3) Arching spring (kombinasi metal spring) (Mulyani dan
Rinawati, 2013).
d) Cara kerja
Menahan sperma agar tidak mendapatkan akses mencapai
saluran alat reproduksi bagian atas (uterus dan tuba falopii)
dan sebagai alat tempat spermisida (Mulyani dan Rinawati,
2013).
e) Manfaat kontrasepsi
(1) Efektif bila digunakan dengan benar
(2) Tidak mengganggu produksi ASI
(3) Tidak mengganggu hubungan seksual karena telah
terpasang sampai 6 jam sebelumnya
240
(4) Tidak menganggu kesehatan pasien (Mulyani dan
Rinawati, 2013).
f) Manfaat nonkontrasepsi
(1) Salah satu perlindungan terhadap IMS/HIV/AIDS,
khususnya apabila digunakan dengan spermisida
(2) Bila digunakan pada saat haid, menampung darah
menstrusi (Mulyani dan Rinawati, 2013).
g) Keterbatasan
(1) Efektivitas sedang (bila digunakan dengan spermisida
angka kegagalan 6-16 kehamilan per 100 perempuan
per tahun pertama), karena bergantung pada kepatuhan
mengikuti cara penggunaan
(2) Motivasi diperlukan berkesinambungan dengan
menggunakannya setiap berhubungan seksual
(3) Pemeriksaan pelvik oleh petugas kesehatan terlatih
diperlukan untuk memastikan ketepatan pemasangan
(4) Pada beberapa pengguna menjadi penyebab infeksi
saluran uretra
(5) Pada 6 jam pascahubungan seksual alat masih harus
berada di posisinya (Mulyani dan Rinawati, 2013).
h) Indikasi diafragma
(1) Tidak menyukai metode kontrasepsi hormonal,
perokok, umur >35 tahun
(2) Tidak menyukai menggunakan IUD
(3) Menyusui dan perlu kontrasepsi
(4) Memerlukan proteksi terhadap IMS
(5) Memerlukan metode sederhana sambil menunggu
metode yang lain (Mulyani dan Rinawati, 2013).
i) Kontraindikasi diafragma
(1) Berdasarkan umur dan paritas serta masalah kesehatan
menyebabkan kehamilan menjadi berisiko tinggi
241
(2) Terinfeksi saluran uretra
(3) Tidak stabil secara psikis atau tidak suka menyentuh
alat kelaminnya (vulva dan vagina)
(4) Mempunyai riwayat sindrom syok karena keracunan
(5) Ingin metode KB efektif (Mulyani dan Rinawati, 2013).
j) Cara menggunakan diafragma
(1) Pertama kosongkan kandung kemih dan cuci tangan
sebelum melakukan hubungan seksual
(2) Gunakan tangan saat membuka kemasan, jangan
menggunakan gigi, benda tajam seperti pisau, silet,
gunting atau benda tajam lainnya
(3) Pastikan diafragma tidak berlubang (tes dengan mengisi
diafragma dengan air, atau melihat menembus cahaya)
(4) Oleskan sedikit spermisida krim atau jelli pada kap
diafragma (untuk memudahkan pemasangan tambahkan
krim atau jelli, remas bersamaan dengn pinggirannya)
(5) Posisi saat pemasangan diafragma boleh sambil
berbaring, sambil jongkok atau satu kakik diangkat ke
atas kursi
(6) Lalu tangan kiri melebarkan kedua bibir vagina,
sedangkan tangan kanan memasang diafragma ke
dalam vagina jauh ke belakang, dorong bagian depan
pinggiran ke atas di balik tulang pubis
(7) Masukkan jari telunjuk tangan kanan ke dalam vagina
sampai menyentuh serviks, sarungkan karetnya dan
pastikan serviks tealh terlindungi
(8) Rapihkan cincin bagian luar yang terbuka di bibir
vagina. Diafragma dipasang di vagina sampai 6 jam
sebelum hubungan seksual. Jika hubungan seksual
berlangsung di atas 6 jam setelah pemasangan
tambahkan spermisida ke dalam vagina
242
(9) Setelah itu diafragma siap dipakai untuk berhubungan
badan suami istri
(10) Untuk melepaskan diafragma tinggal cabut pelan-pelan
dan lapisan bagian cincin yang luar dipencet agar
sperma tidak berantakan kemana-mana. Diafragma
berada di dalam vagina paling tdak 6 jam setelah
hubungan seksual. Jangan tinggalkan diafragma di
dalam vagina lebih dari 24 jam sebelum diangkat (tidak
dianjurkan mencuci vagina setiap wkatu, pencucian
vagina bisa dilakukan setelah ditunda 6 jam sesudah
hubungan seksual)
(11) Cuci dengan sabun dan air lalu keringkan sebelum
dibuang atau segera setelah diafragma dilepas ikat
pangkalnya dengan kuat lalu dibuang pada tempatnya
(Mulyani dan Rinawati, 2013).
243
Tabel 2.18 Penanganan Efek Samping Diafragma Efek Samping Penanganan
Infeksi saluran uretra Pengobatan dengan antibiotik yang
sesuai, apabila diafragma menjadi pilihan
utama dalam ber-KB. Sarankan untuk
segera mengosongkan kandung kemih
setelah melakukan hubungan seksual
atau sarankan memakai metode lain
Dugaan adanya reaksi alergi diafragma
atau dugaan adanya reaksi alergi
spermisida
Walaupun jarang terjadi, terasa kurang
nyaman dan mungkin berbahaya. Jika
ada gejala iritasi vagina, khususnya
pascasenggama, dan tidak mengidap
IMS, berikan spermisida yang lain atau
bantu untuk memilih metode yang lain
Rasa nyeri pada tekanan terhadap
kandung kemiih atau rectum
Pastikan ketepatan letak diafragma
apabila alat terlalu besar. Cobalah
dengan ukuran yang lebih kecil.
Tindaklanjuti untuk meyakinkan masalah
telah ditangani. Pastikan ketepatan letak
diafragma apabila alat terlalu besar.
Cobalah dengan ukuran yang lebih kecil.
Tindaklanjuti untuk meyakinkan masalah
telah ditangani
Timbul cairan vagina dan berbau jika
dibiarkan lebih dari 24 jam
Periksa adanya IMS atau benda asing
dalam vagina (tampon dll), jika tidak
ada, sarankan klien untuk melepas
diafragma setelah melakukan hubungan
seksual, tapi tidak kurang dari 6 jam
setelah aktivitas terakhir. Setelah
diangkat (diafragma harus dicuci dengan
hati-hati menggunakan sabun cair dan
air, jangan menggunakan bedak atau talk
jika akan disimpan). Jika mengidap IMS,
lakukan pemprosesan alat sesuai dengan
pencegahan infeksi
Sumber: Mulyani dan Rinawati, 2013, Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi, Bagian
Metode Barier, Yogyakarta, halaman 66-67.
5) Senggama terputus/Coitus interuptus
Metode lain dair coitus interuptus adalah senggama terputus
atau ekspulsi pra ejakulasi atau pancaran ekstra vaginal atau
withdrawal methods atau pull-out method. Dalan bahasa latin
disebut juga interrupted intercourse (Mulyani dan Rinawati,
2013).
a) Pengertian
Coitus interuptus atau senggama terputus adalah metode KB
tradisional atau alamiah, di mana pria mengeluarkan alat
244
kelaminnya (penis) dari vagina sebelum mencapai ejakulasi
(Mulyani dan Rinawati, 2013).
b) Cara kerja
Alat kelamin (penis) dikeluarkan sebelum ejakulasi
sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina, maka tidak
ada pertemuan antara sperma dan ovum, dan kehamilan
dapat dicegah. Ejakulasi di luar vagina untuk mengurangi
kemungkinan air mani mencapai uterus (Mulyani dan
Rinawati, 2013).
c) Efektifitas
Metode coitus interuptus akan efektif apabila dilakukan
dengan benar dan konsisten. Angka kegagalan 4-27
kehamilan per 100 perempuan per tahun. Pasangan yang
mempunyai pengendalian diri yang besar, pengalaman dan
kepercayaan dapat menggunakan metode ini menjadi lebih
efektif (Mulyani dan Rinawati, 2013).
d) Manfaat kontrasepsi
(1) Alamiah
(2) Efektif bila dilakukan dengan benar
(3) Tidak mengganggu produksi ASI
(4) Tidak ada efek samping
(5) Tidak membutuhkan biaya
(6) Tidak memerlukan persiapan khusus
(7) Dapat dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lain
(8) Dapat digunakan setiap waktu (Mulyani dan Rinawati,
2013).
e) Manfaat non kontrasepsi
(1) Adanya peran serta suami dalam keluarga berencana
dan kesehatan reproduksi
(2) Menanamkan sifat saling pengertian
245
(3) Tanggung jawab bersama dalam ber-KB (Mulyani dan
Rinawati, 2013).
f) Keterbatasan
(1) Sangat tergantung dari pihak pria dalam mengontrol
ejakulasi dan tumpahan sperma selama senggama
(2) Memutus kenikmatan dalam berhubungan seksual
(orgasme)
(3) Sulit mengontrol tumpahan sperma selama penetrasi,
sesaat dan setelah coitus interupsi
(4) Tidak melindungi dari penyakit menular seksual
(5) Kurang efektif untuk mencegah kehamilan (Mulyani
dan Rinawati, 2013).
g) Cara Coitus Interuptus
(1) Sebelum melakukan hubungan seksual, pasangan harus
saling membangun kerjasama dan pengertian terlebih
dahulu. Keduanya harus mendiskusikan dan sepakat
untuk menggunakan metode senggama terputus
(2) Sebelum melakukan hubungan seksual, suami harus
mengosongkan kandung kemih dan membersihkan
ujung penis untuk menghilangkan sperma dari ejakulasi
sebelumnya
(3) Apabila merasa akan ejakulasi, suami segera
mengeluarkan penisnya dari vagina pasangannya dan
mengeluarkan sperma di luar vagina
(4) Pastikan tidak ada tumpahan sperma selama senggama
(5) Pastikan suami tidak terlambat melaksanaknnya
(6) Senggama dianjurkan tidak dilakukan pada masa subur
(Mulyani dan Rinawati, 2013).
246
6) Implant
a) Pengertian
Kontrasepsi implant adalah alat kontrasepsi yang dipasang
dibawah kulit. Implant adalah suatu alat kontrasepsi yang
mengandung levonorgetrel yang dibungkus dalam kapsul
silastic silicon(polydimethylsiloxane) dan dipasang dibawah
kulit. (Mulyani dan Rinawati, 2013).
b) Efektifitas
Efektif lima tahun untuk norplant dan tiga tahun untuk
Jadena, Indoplant, atau Implanon. Sangat efektif (kegagalan
0,2-1 kehamilan per 100 perempuan) (Sulistyawati, 2013).
c) Jenis
(1) Norplant. Terdiri atas enam batang silastik lembut
berongga dengan panjang 3,4 cm dengan diameter 2,4
mm yang diisi dengan 36 mg levonorgestrel. Lama
kerjanya lima tahun.
(2) Implanon. Terdiri atas satu batang putih lentur dengan
panjang kira-kira 40 mm dan diameter 2 mm, yang diisi
dengan 68 mg 3-keto-desogestrel dan lama kerjanya
tiga tahun.
(3) Jadena dan Indoplant. Terdiri atas dua batang yang
berisi 75 mg levonorgestrel dengan lama kerja tiga
tahun (Sulistyawati, 2013).
d) Cara kerja
(1) Lendir serviks menjadi kental
(2) Mengganggu proses pembentukan endometrium
sehingga sulit terjadi implantasi
(3) Mengurangi transportasi sperma
(4) Menekan ovulasi (Sulistyawati, 2013).
e) Keuntungan
(1) Perlindungan jangka panjang (sampai lima tahun)
247
(2) Pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah
pencabutan
(3) Tidak memerlukan pemeriksaan dalam
(4) Bebas dari pengaruh esterogen
(5) Tidak mengganggu aktivitas seksual
(6) Tidak menganggu produksi ASI
(7) Klien hanya perlu kembali ke klinik bila ada keluhan
(8) Dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan
(Sulistyawati, 2013).
f) Keterbatasan
Pada kebanyakan klien metode ini dapat menyebabkan
perubahan pola haid berupa perdarahan bercak (spotting),
hipermenorea atau meningkatnya jumlah darah haid, serta
menorea. Timbulnya keluhan-keluhan sebagai berikut:
(1) Nyeri kepala
(2) Peningkatan/penurunan berat badan
(3) Nyeri payudara
(4) Perasaan mual
(5) Pening/pusing kepala
(6) Perubahan perasaan (mood) atau kegelisahan
(7) Membutuhkan tindakan pembedahan minor untuk
insersi dan pencabutan
(8) Tidak memberikan efek protektif terhadap infeksi
menular seksual termasuk AIDS
(9) Klien tidak dapat mengehntikan sendiri pemakaian
kontrasepsi ini sesuai dengan keinginan, akan tetapi
harus pergi ke klinik untuk pencabutan
(10) Efektivitasnya menurun bila menggunakan obat-obat
tuberkulosis (rifampisin) atau obat epilepsi (fenitoin
dan barbiturat)
248
(11) Terjadinya kehamilan ektopik sedikit lebih tinggi (1,3
per 100.000 perempuan per tahun) (Sulistyawati, 2013).
g) Klien yang boleh menggunakan implan
(1) Perempuan pada usia reproduksi
(2) Telah memiliki anak ataupun yang belum
(3) Menghendaki kontasepsi yang memiliki efektivitas
tinggi dan menghendaki pencegahan kehamilan jangka
panjang
(4) Menyusui dan membutuhkan kontrasepsi
(5) Pascapersalinan dan tidak menyusui
(6) Pascakeguguran
(7) Tidak menginginkan anak lagi, tetapi menolak
sterilisasi
(8) Riwayat kehamilan ektopik
(9) Tekanan darah dibawah 180/110 mmHg, dengan
masalah pembekuan darah atau anemia bulan sabit
(sickle cell)
(10) Perempuan yang tidak boleh menggunakan kontrasepsi
hormonal yang mengandung esterogen
(11) Perempuan yang sering lupa menggunakan pil
(Sulistyawati, 2013).
h) Klien yang tidak boleh menggunakan implan
(1) Hamil atau diduga hamil
(2) Perempuan dengan perdarahan pervaginam yang belum
jelas penyebabnya
(3) Memiliki benjolan/kanker payudara atau riwayat
kanker payudara
(4) Perempuan yang tidak dapat menerima perubahan pola
haid yang terjadi
(5) Memiliki miom uterus dan kanker payudara
249
(6) Mengalami gangguan tolerasnsi glukosa (Sulistyawati,
2013).
7) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau IUD
a) Pengertian
IUD singkatan dari Intra Uterine Device yang merupakan
alat kontrasepsi paling banyak digunakan, karena dianggap
sangat efektif dalam mencegah kehamilan dan memiliki
manfaat yang relatif banyak dibanding alat kontrasepsi
lainnya. Diantaranya tidak mengganggu saat coitus
(hubungan badan), dapat digunakan sampai menopause dan
setelah IUD dikeluarkan dari rahim, bisa dengan mudah
subur (Mulyani dan Rinawati, 2013).
b) Efektifitas IUD
AKDR/IUD efektif mencegah kehamilan dari 98% hingga
mencapai hampir 100%, yang bergantung pada alatnya.
AKDR terbaru, seperti T380A, memiliki angka kegagalan
yang jauh lebih rendah pada semua tahap pemakaian tanpa
ada kehamilan setelah 8 tahun pemakaian. Pada sebuah
studi, angka kehamilan kumulatif setelah 12 tahun adalah
2,2 per 100 pengguna, 0,4 di antaranya adalah kehamilan
ektopik (Subekti, 2013).
c) Jenis IUD
Jenis IUD bermacam-macam, paling umum dulu dikenal
dengan nama spiral. Jenis-jenis IUD meliputi:
(1) Lippes-Loop
(2) Saf-T-Coil
(3) Dana-Super
(4) Copper-T (Gyne-T)
(5) Copper-7 (Gravigard)
(6) Multiload
(7) Progesterone IUD
250
Dari berbagai jenis IUD di atas, saat ini yang umum beredar
dipakai Indonesia ada 3 macam jenis yaitu :
(1) IUD Copper T, terbentuk dari rangka plastik yang
lentur dan tembaga yang berada pada kedua lengan
IUD dan batang IUD.
Gambar 2.8 IUD Copper T Sumber: Mulyani dan Rinawati, 2013, Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi, Bagian
Intra uterine Device, Yogyakarta, Halaman 101.
(2) IUD Nova T, terbentuk dari rangka plastik dan
tembaga. Pada ujung lengan IUD bentuknya agak
melengkung tanpa ada tembaga, tembaga hanya ada
pada batang IUD.
Gambar 2.9 IUD Nova T Sumber: Mulyani dan Rinawati, 2013, Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi, Bagian
Intra uterine Device, Yogyakarta, Halaman 101.
(3) IUD Mirena, terbentuk dari rangka plastik yang
dikelilingi oleh silinder pelepas hormon Levonolgestrel
251
(hormon progesteron) sehingga IUD ini dapat dipakai
oleh ibu menyusui karena tidak menghambat ASI
(Mulyani dan Rinawati, 2013).
Gambar 2.10 IUD Mirena Sumber: Mulyani dan Rinawati, 2013, Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi, Bagian
Intra uterine Device, Yogyakarta, Halaman 101.
d) Cara kerja IUD
(1) Cara kerja utama mencegah sperma bertemu sel telur
(2) Mencegah implantasi atau tertanamnya sel telur dalam
rahim
(3) Untuk IUD Mirena ada tambahan cara kerjanya yaitu
mengentalkan lendir rahim karena pengaruh hormon
Levonolgestrel yang dilepaskannya (Mulyani dan
Rinawati, 2013).
e) Keuntungan IUD
(1) Sebagai kontrasepsi, efektivitasnya tinggi (1 kegagalan
dalam 125-170 kehamilan)
(2) Dapat efektif segera setelah pemasangan
(3) IUD merupakan metode kontrasepsi jangka panjang
(4) Tidak tergantung pada daya ingat
(5) Tidak mempengaruhi hubungan seksual
(6) Tidak ada interaksi dengan obat-obatan
252
(7) Membantu mencegah kehamilan di luar kandungan
(kehamilan ektopik) (Mulyani dan Rinawati, 2013).
f) Kerugian IUD
(1) Pemeriksaan dalam dan penyaringan infeksi saluran
genetalia diperlukan sebelum pemasangan IUD
(2) Perdarahan di antara haid (spotting)
(3) Setelah pemasangan, kram dapat terjadi dalam
beberapa hari
(4) Dapat meningkatkan risiko penyakit radang panggul
(5) Memerlukan prosedur pencegahan infeksi sewaktu
memasang dan mencabutnya
(6) Haid semakin banyak, lama dan rasa sakit selama 3
bulan pertama pemakaian IUD dan berkurang setelah 3
bulan
(7) Pasien tidak dapat mencabut sendiri IUD-nya
(8) Tidak melindungi pasien terhadap PMS (Penyakit
Menular Seksual), AIDS atau HIV
(9) IUD dapat keluar rahim melalui kanalis hingga keluar
vagina (Mulyani dan Rinawati, 2013).
g) Yang dapat memakai IUD
(1) Usia reproduktif
(2) Keadaan nulipara (yang belum mempunyai anak)
(3) Menginginka kontrasepsi jangka panjang
(4) Ibu yang sedang menyusui
(5) Setelah mengalami keguguran dan tidak terlihat adanya
infeksi
(6) Risiko rendah IMS
(7) Tidak menghendaki metode kontrasepsi hormonal
(Mulyani dan Rinawati, 2013).
h) Yang tidak bisa memakai IUD
(1) Kemungkinan hamil
253
(2) Setelah melahirkan (2-28 hari pasca melahirkan),
pemasangan IUD hanya boleh dilakukan sebelum
48jam dan setelah 4 minggu pascapersalinan
(3) Memiliki risiko IMS (termasuk HIV), yang berisiko
terinfeksi IMS/HIV yaitu:
(a) Yang mempunyai lebih dari 1 pasangan tidak selalu
memakai kondom
(b) Yang memiliki pasangan dengan HIV/IMS dan
tidak selalu memakai kondom
(c) Memakai jarum suntik bersama, atau pasangan
memakai jarum suntik (hanya untuk HIV tetapi
tidak untuk IMS
(4) Perdarahan vagina yang tidak diketahui
(5) Sedang menderita infeksi alat genital
(6) Tiga bulan terakhir sedang mengalami atau sering
menderita penyakit radang panggul atau infeksi setelah
keguguran (Mulyani dan Rinawati, 2013).
i) Waktu pemasangan IUD
(1) IUD dapat di pasang kapan saja dalam siklus haid
selama yakin tidak hamil
(2) Pemasangan setelah persalinan, boleh dipasang dalam
waktu 48 jam setelah persalinan
(3) Dapat pula dipasang setelah 4 minggu pasca persalinan,
dengan dipastikan tidak hamil
(4) Antara 48 jam sampai 4 minggu pasca persalinan, tunda
pemasangan, gunakan metode kontrasepsi yang lain
(5) Setelah keguguran atau aborsi, jika mengalami
keguguran dalam 7 hari terakhir, boleh dipasang jika
tidak ada infeksi. Jika keguguran lebih dari 7 hari
terakhir, boleh dipasang jika dipastikan tidak hamil
254
(6) Jika terjadi infeksi, boleh dipasang 3 bulan setelah
sembuh.
(7) Jika ganti dari metode yang lain, jika telah memakai
metode lain dengan benar atau tidak bersenggama sejak
haid terakhir, AKDR boleh dipasang. (Tidak hanya
selama haid, termasuk melakukan MAL dengan benar)
(Mulyani dan Rinawati, 2013).
j) Cara memeriksa benang IUD
(1) Ibu datang ke tenaga kesehatan
(2) Memeriksa sendiri dengan cara :
(a) Cuci tangan
(b) Masukkan jari ke dalam vagina dan rasakan benang
di mulut rahim
(c) Cuci tangan setelah selesai (Mulyani dan Rinawati,
2013).
8) Suntik Tribulan atau Progestin
a) Pengertian
Suntik tribulan merupakan metode kontrasepsi yang
diberikan secara intramuscular setiap tiga bulan. Keluarga
berencana suntik merupakan metode kontrasepsi efektif
yaitu metode yang dalam penggunaanya mempunyai
efektifitas atau tingkat kelangsungan pemakaian relatif lebih
tinggi serta angka kegagalan relatif lebih rendah bila
dibandingkan dengan alat kontrasepsi sederhana (Mulyani
dan Rinawati, 2013).
b) Jenis kontrasepsi tribulan
Yang termasuk dalam metode suntikan tribulan yaitu:
(1) DMPA (Depot medroxy progesterone acetate) atau
Depo Provera yang diberikan tiap tiga bulan dengan
dosis 150 miligram yang disuntik secara IM.
255
(2) Depo Noristerat diberikan setiap 2 bulan dengan dosis
200 mg Nore-tindron Enantat (Mulyani dan Rinawati,
2013).
c) Cara kerja
Mekanisme metode suntik KB tribulan yaitu:
(1) Menghalangi terjadinya ovulasi dengan jalan menekan
pembentukan releasing factor dari hipotalamus
(2) Leher serviks bertambah kental, sehingga menghambat
penetrasi sperma melalui serviks uteri
(3) Menghambat implantasi ovum dalam endometrium
(Mulyani dan Rinawati, 2013).
d) Efektifitas
Efektifitas keluarga berencana suntik tribulan sangat tinggi,
angka kegagalan kurang dari 1 %. World Health
Organization (WHO) telah melakukan penelitian pada
DMPA (Depot medroxy progesterone acetate) dengan dosis
standart dengan angka kegagalan 0,7 % , asal
penyuntikannya dilakukan secara teratur sesuai jadwal yang
ditentukan (Mulyani dan Rinawati, 2013).
e) Keuntungan metode suntik tribulan
(1) Efektifitas tinggi
(2) Sederhana pemakaiannya
(3) Cukup menyenangkan bagi akseptor (injeksi hanya 4
kali dalam setahun)
(4) Cocok untuk ibu-ibu yang menyuusi anak
(5) Tidak berdampak serius terhadap penyakit gangguan
pembekuan darah dan jantung karena tidak
mengandung hormon estrogen
(6) Dapat mencegah kanker endometrium, kehamilan
ektopik, serta beberapa penyebab penyakit akibat
radang panggul
256
(7) Menurunkan krisis anemia bulan sabit (sickle cell)
(Mulyani dan Rinawati, 2013).
f) Kekurangan metode suntik tribulan
(1) Terdapat gangguan haid seperti amenore yaitu tidak
datang haid pada setiap bulan selama menjadi akseptor
keluarga berencana suntik tiga bulan berturut-turut.
Spoting yaitu bercak-bercak perdarahan di luar haid
yang terjadi selama akseptor mengikuti keluarga
berencana suntik. Metroragia yaitu perdarahan yang
berlebihan diluar masa haid. Menoragia yaitu
datangnya darah haid yang berlebih jumlahnya
(2) Timbulnya jerawat di badan atau wajah dapat disertai
infeksi atau tidak bila digunakan dalam jangka panjang
(3) Berat badan yang bertambah 2,3 kg pada tahun pertama
dan meningkat 7,5 kg selama enam tahun
(4) Pusing dan sakit kepala
(5) Bisa menyebabkan warna biru dan rasa nyeri pada
daerah suntikan akibat perdarahan bawah kulit
(Mulyani dan Rinawati, 2013).
g) Yang dapat menggunakan suntik tribulan
(1) Ibu usia reproduksi (20-35 tahun)
(2) Ibu pascapersalinan
(3) Ibu pasca keguguran
(4) Ibu yang tidak dapat mengggunakan kontrasepsi yang
mengandung estrogen
(5) Nulipara dan yang telah mempunyai anak banyak serta
belum bersedia untuk KB tubektomi
(6) Ibu yang sering lupa menggunakan KB pil
(7) Anemia defisiensi besi
(8) Ibu yang tidak memiliki riwayat darah tinggi
257
(9) Ibu yang sedang menyusui (Mulyani dan Rinawati,
2013).
h) Yang tidak dapat menggunakan suntik tribulan
(1) Ibu hamil atau dicurigai hamil
(2) Ibu yang menderita kanker payudara atau riwayat
kanker payudara
(3) Diabetes mellitus yang disertai komplikasi
(4) Perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya
(Mulyani dan Rinawati, 2013).
i) Waktu yang diperbolehkan untuk penggunaan KB suntik
tribulan
(1) Mulai hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid
(2) Bila suntikkan pertama diberikan setelah hari ke 7
siklus haid dan pasien tidak hamil. Pasien tidak boleh
melakukan hubungan seksual untuk 7 hari lamanya atau
penggunaan metode kontrasepsi yang lain selama masa
waktu 7 hari
(3) Jika pasien pascapersalinan > 6 bulan, menyusui, serta
belum haid, suntikan pertama dapat diberikan, asal
dipastikan tidak hamil
(4) Bila pascapersalinan 3 minggu dan tidak menyusui,
suntikan kombinasi dapat diberikan
(5) Ibu pasca keguguran, suntikan progestin dapat
diberikan
(6) Ibu dengan menggunakan metode kontrasepsi hormonal
yang lain dan ingin mengganti dengan kontrasepsi
hormonal progestin, selama ibu tersebut menggunakan
kontrasepsi sebelumnya secara benar, suntikan
progestin dapat segera diberikan tanpa menunggu haid.
Bila ragu-ragu perlu dilakukan uji kehamilan terlebih
dahulu
258
(7) Bila kontrasepsi sebelumnya juga kontrasepsi
hormonal, dan ibu tersebut ingin mengganti dengan
suntikan kombinasi, maka suntikan kombinasi tersebut
dapat diberikan sesuai jadwal kontrasepsi sebelumnya.
Tidak diperlukan metode kontrasepsi lain.
(8) Ibu menggunakan metode kontrasepsi non hormonal
dan ingin menggantinya dengan suntikan kombinasi,
maka suntikan pertama dapat diberikan asal saja
diyakini ibu tersebut tidak hamil dan pemberianya
tanpa menunggu datangnya haid. Bila diberikan pada
hari 1-7 siklus haid metode kontrasepsi lain tidak
diperlukan. Bila sebelumnya IUD dan ingin
menggantinya dengan suntikkan kombinasi, maka
suntikan pertama diberikan hari 1-7 siklus haid. Cabut
segera IUD (Mulyani dan Rinawati, 2013).
9) Mini pil
a) Pengertian
Mini pil adalah pil KB yang hanya mengandung hormon
progesteron dalam dosis rendah. Mini pil atau pil progestin
disebut juga pil menyusui. Dosis progestin yang digunakan
0,03-0,05 mg per tablet (Mulyani dan Rinawati, 2013).
b) Jenis mini pil
Mini pil terbagi dalam 2 jenis yaitu:
(1) Mini pil dalam kemasan dengan isi 28 pil: mengandung
75 mikro gram desogestrel
(2) Mini pil dalam kemasan dengan isi 35 pil: mengandung
300 mikro gram levonogestrel atau 350 mikro gram
noretindron (Mulyani dan Rinawati, 2013).
c) Cara kerja mini pil
Cara kerja dari kontrasepsi pil progestin atau mini pil dalam
mencegah kehamilan antara lain dengan cara:
259
(1) Menghambat ovulasi
(2) Mencegah implantasi
(3) Mengentalkan lendir serviks sehingga menghambat
penetrasi sperma
(4) Mengubah motilitas tuba sehingga transportasi sperma
menjadi terganggu (Mulyani dan Rinawati, 2013).
d) Efektifitas mini pil
Pil progestin atau mini pil sangat efektif (98,5%) untuk
digunakan pada ibu menyusui bila penggunaan yang benar
dan konsisten sangat mempengaruhi tingkat efektifitasnya.
Efektifitas penggunaan mini pil akan berkurang pada saat
mengkonsumsi obat anti konvulsan (fenitoin),
carbenzemide, barbiturat, dan obat anti tuberkulosis
(rifampisin) (Mulyani dan Rinawati, 2013).
e) Kerugian mini pil
(1) Memerlukan biaya
(2) Harus selalu tersedia
(3) Efektifitas berkurang apabila menyusui juga berkurang
(4) Penggunaan mini pil bersamaan dengan obat
tuberkulosis atau epilepsi akan mengakibatkan
efektifitas menjadi rendah
(5) Mini pil harus diminum setiap hari dan pada waktu
yang sama
(6) Angka kegagalan tinggi apabila penggunaan tidak
benar dan konsisten
(7) Tidak melindungi dari penyakit menular seksual
termasuk HBV dan HIV/AIDS
(8) Mini pil tidak menjamin akan melindungi dari kista
ovarium bagi wanita yang pernah mengalami
kehamilan ektopik (Mulyani dan Rinawati, 2013).
260
f) Keuntungan mini pil
(1) Cocok sebagai alat kontrasepsi untuk perempuan yang
sedang menyusui
(2) Sangat efektif untuk masa laktasi
(3) Dosis gestagen rendah
(4) Tidak menurunkan produksi ASI
(5) Tidak mengganggu hubungan seksual
(6) Kesuburan cepat kembali
(7) Tidak memberikan efek samping estrogen
(8) Tidak ada bukti peningkatan risiko penyakit
kardiovaskuler, risiko tromboemboli vena dan risiko
hipertensi
(9) Cocok untuk perempuan yang menderita diabetes
mellitus
(10) Cocok untuk perempuan yang tidak biasa
mengkonsumsi estrogen
(11) Dapat mengurangi disminorrhea (Mulyani dan
Rinawati, 2013).
g) Efeksamping penggunaan mini pil
Efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan pil
progestin atau mini pil antara lain:
(1) Gangguan haid seperti: perdarahan bercak, spotting,
amenorea dan haid tidak teratur
(2) Peningkatan atau penurunan (fluktuasi) berat badan
(3) Nyeri tekan payudara
(4) Mual
(5) Pusing
(6) Perubahan mood
(7) Dermatitis atau jerawat
(8) Kembung
(9) Depresi
261
(10) Hirsutisme (pertumbuhan rambut atau bulu yang
berlebihan pada daerah muka) tetapi sangat jarang
(Mulyani dan Rinawati, 2013).
h) Indikasi penggunaan mini pil
Kriteria yang boleh menggunakan pil progestin atau mini
pil antara lain:
(1) Wanita usia reproduksi (20-35 tahun)
(2) Wanita yang telah memiliki anak maupun yang belum
mempunyai anak
(3) Pasca persalinan dan tidak sedang menyusui
(4) Menginginkan metode kontrasepsi efektif selama masa
menyusui
(5) Ibu pasca keguguran
(6) Tekanan darah kurang dari 180/110 mmHg atau dengan
masalah pembekuan darah
(7) Tidak boleh mengkonsumsi estrogen atau lebih senang
menggunakan progestin
(8) Perokok segala usia (Mulyani dan Rinawati, 2013).
i) Kontra indikasi penggunaan mini pil
Kriteria yang tidak boleh menggunakan kontrasepsi pil
progestin atau mini pil antara lain:
(1) Wanita usia tua dengan perdarahan yang tidak
diketahui penyebabnya (lebih dari 35 tahun)
(2) Wanita yang diduga hamil
(3) Tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid
(4) Riwayat kehamilan ektopik
(5) Riwayat kanker payudara atau penderita kanker
payudara
(6) Wanita pelupa sehingga sering tidak minum pil
(7) Gangguan tromboemboli aktif (bekuan di tungkai, paru
atau mata)
262
(8) Ikterus, penyakit hati aktif atau tumor hati jinak
maupun ganas
(9) Wanita dengan miom uterus
(10) Riwayat stroke
(11) Perempuan yang sedang mengkonsumsi obat-obat
untuk tuberculosis dan epilepsi (Mulyani dan Rinawati,
2013).
10) Kontrasepsi mantap
a) Pengertian
Kontrasepsi mantap merupakan salah satu metode
kontrasepsi yang dilakukan dengan cara mengikat atau
memotong saluran telur (pada perempuan) dan saluran
sperma (pada laki-laki). Karena sifatnya yang permanen,
kontrasepsi ini hanya diperkenankan bagi mereka yang
sudah mantab memutuskan untuk tidak lagi mempunyai
anak (Mulyani dan Rinawati, 2013).
Sterilisasi ialah tindakan yang dilakukan pada kedua tuba
fallopii perempuan atau kedua vas deferens laki-laki, yang
mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hamil atau
tidak menyebabkan kehamilan lagi (Prawirohardjo, 2014).
b) Jenis kontrasepsi mantap
(1) Tubektomi
(a) Pengertian
Tubektomi adalah setiap tindakan pada kedua
saluran telur wanita yang mengakibatkan orang
yang bersangkutan tidak akan mendapatkan
keturunan lagi (Mulyani dan Rinawati, 2013).
Sterilisasi wanita dilakukan dengan cara eksisi atau
menghambat tuba falopii yang membawa ovum
dari ovarium ke uterus. Tindakan ini mencegah
263
ovum dibuahi oleh sperma di tuba falopii (Subekti,
2013).
(b) Efektifitas
Kontrasepsi yang sangat efektif dengan angka
kegagalan 1-5 per 1000 kasus, yang berarti
efektifitasnya 99,4 – 99,8 % per 100 wanita per
tahun (Subekti, 2013).
(c) Jenis tubektomi
1) Minilaparotomi
Metode ini merupakan pengambilan tuba yang
dilakukan melalui sayatan kecil (sekitar 3 cm)
baik pada daerah bawah perut (suprapubik)
maupun pada lingkar pusat bawah (sub
umbilikal), baik dilakukan untuk masa interval
maupun pascapersalinan.
2) Laparoskopi
Laparoskopi dapat dilakukan 6-8 minggu
pascapersalinan atau setelah abortus.
Laparoskopi sebaiknya digunakan untuk
jumlah pasien yang memadai karena peralatan
dan biaya pemeliharaan cukup mahal (Mulyani
dan Rinawati, 2013).
(d) Cara kerja
Cara kerja tubektomi atau ligasi tuba yaitu dengan
mengonklusi tuba falopii (mengikat dan memotong
atau memasang cincin) sehingga sperma tidak
dapat bertemu dengan ovum (Mulyani dan
Rinawati, 2013).
(e) Indikasi tubektomi
1) Umur lebih dari 26 tahun
2) Anak lebih dari 2 orang
264
3) Yakin telah mempunyai keluarga dengan
jumlah yang diinginkan
4) Ibu pascapersalinan
5) Ibu pascakeguguran
6) Pasien paham dan setuju dengan prosedur KB
tubektomi terutama pengetahuan pasangan
tentang cara-cara kontrasepsi ini, risiko dan
keuntungan kontrasepsi tubektomi dan
pengetahuan tentang sifat permanennya
kontrasepsi ini (Mulyani dan Rinawati, 2013).
(f) Kontraindikasi tubektomi
1) Masalah hubungan
2) Ketidaksetujuan terhadap operasi dari salah
satu pasangan
3) Penyakit psikiatrik
4) Keadaan sakit atau disabilitas yang dapat
meningkatkan risiko pada saat operasi
(Subekti, 2013).
(g) Keuntungan tubektomi
1) Efektifitasnya tinggi
2) Permanen
3) Efektif dengan segera (Subekti, 2013).
(h) Kerugian tubektomi
1) Melibatkan prosedur pembedahan dan anastesi
2) Tidak mudah kembali subur (Subekti, 2013).
(i) Efek samping
1) Jika ada kegagalan metode maka ada risiko
tinggi kehamilan ektopik
2) Merasa berduka dan kehilangan (Subekti,
2013).
265
(2) Vasektomi
(a) Pengertian
Vasektomi adalah pemotongan vas deferens, yang
merupakan saluran yang mengangkut sperma dari
epididimis di dalam testis ke vesikula seminalis.
Dengan memotong vas deferens, sperma tidak
mampu diejakulasikan dan pria akan menjadi tidak
subur setelah vas deferens bersih dari sperm, yang
memakan waktu sekitar tiga bulan (Subekti, 2013).
(b) Efektifitas
Vasektomi adalah bentuk kontrasepsi yang sangat
efektif. angka kegagalan langsungnya adalah 1
dalam 1000; angka kegagalan lanjutnya adalah
antara 1 dalam 3000 dan 1 dalam 7000 (Subekti,
2013).
(c) Jenis-jenis vasektomi
1) Vasektomi Tanpa Pisau (VTP atau No-scalpel
Vasektomi)
2) Vasektomi dengan insisi skrotum (tradisional)
3) Vasektomi semi permanen (pengikatan vas
deferens) (Mulyani dan Rinawati, 2013).
(d) Kerugian vasektomi
1) Diperlukan kontrasepsi alternatif sampai
didapat dua kali hitung sperma bersih secara
berurutan
2) Diperlukan prosedur pembedahan
3) Dibutuhkan anastesia lokal atau anastesi
umum
4) Tidak mudah untuk kembali subur (Subekti,
2013).
266
(e) Keuntungan vasektomi
1) Metode permanen
2) Efektifitas tinggi
3) Menghilangkan kecemasan akan terjadinya
kehamilan yang tidak direncanakan
4) Prosedur aman dan sederhana (Subekti, 2013).
(f) Syarat vasektomi
1) Sukarela, artinya pasien telah mengerti dan
memahami segala akibat prosedur vasektomi
selanjutnya memutuskan pilihannya atas
keinginan sendiri, dengan mengisi dan
menandatangani informed consent.
2) Concent (persetujuan tindakan)
a) Bahagia, artinya pasien terikat dalam
perkawinan yang sah dan telah
mempunyai anak minimal 2 orang dengan
umur anak terkecil minimal 2 tahun
b) Sehat, melalui pemeriksaan oleh dokter
pasien dianggap sehat dan memenuhi
persyaratan medis untuk dilakukan
prosedur tindakan vasektomi (Mulyani
dan Rinawati, 2013).
(g) Kontraindikasi mutlak
1) Ketidakmampuan fisik yang serius
2) Masalah urologi (Subekti, 2013).
d. Tujuan Program KB
Tujuan umumnya adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan
kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga, dengan cara pengaturan
kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera
yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan lain meliputi
267
pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga. (Sulistyawati, 2013).
e. Ruang Lingkup Program KB
Ruang lingkup program KB mencakup sebagai berikut:
1) Ibu
Dengan jalan mengatur jumlah dan jarak kelahiran. Adapun
manfaat yag diperoleh oleh ibu adalah sebagai berikut
a) Tercegahnya kehamilan yang berulang kali dalam jangka
waktu yang terlalu pendek, sehingga kesehatan ibu dapat
terpelihara terutama kesehatan organ reproduksinya
b) Meningkatkan kesehatan mental dan sosial yang
dimungkinkan oleh adanya waktu yang cukup untuk
mengasuh anak-anak dan beristirahat yang cukup karena
kehadiran akan anak tersebut memang diinginkan
2) Suami
Dengan memberikan kesempatan suami agar dapat melakukan
hal berikut.
a) Memperbaiki kesehatan fisik
b) Mengurangi beban ekonomi keluarga yang ditanggungnya
3) Seluruh keluarga
Dilaksanakannya program KB dapat meningkatkan kesehatan
fisik, mental, dan sosial setiap anggota keluarga dan bagi anak
dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar dalam hal
pendidikan serta kasih sayang orang tuanya
Ruang lingkup KB secara umum adalah sebagai berikut:
1) Keluarga berencana
2) Kesehatan reproduksi remaja
3) Ketahanan dan pemberdayaan keluarga
4) Penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas
5) Keserasian kebijakan kependudukan
6) Pengelolaan SDM aparatur (Sulistyawati, 2013).
268
2. Konsep Dasar Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana
a. Pengkajian Data
1) Data subyektif
a) Biodata
(1) Nama
Mengetahui nama klien dan suami berguna untuk
memperlancar komunikasi dalam asuhan sehingga tidak
terlihat kaku dan lebih akrab (Walyani, 2015).
(2) Umur
Peserta KB dari pasangan usia subur berumur 15-29
tahn dengan juamlah anak 2 orang atau 15-28 tahun
dengan juamlah anak 3 atau lebuh, serta beerumur 30-
49 tahun baik yang belum atau sudah punya anak 1
(Handayani, 2010).
(3) Agama
Di berbagai daerah kepercayaan religius dapat
memengaruhi klien dalam memilih metode (Handayani,
2010)
(4) Pendidikan
Tingkat pendidikan tidak saja memengaruhi kerelaan
menggunakan keluarga berencana tetapi juga pemilihan
suatu metode (Handayani, 2010). Makin rendah
pendidikan masyarakat, semakin efektif metode KB
yang dianjurkan yaitu kontap, suntikan KB, susuk KB
atau AKBK (alat susuk bawah kulit), AKDR
(Manuaba, 2010).
(5) Pekerjaan
Hal ini untuk mengetahui taraf hidup dan social
ekonomi agar nasehat kita sesuai.(Roumali, 2011).
Tinggi rendahnya status social dan ekonomi penduduk
269
Indonesia akan memengaruhi perkembangan dari
kemajuan program KB (Handayani, 2010).
(6) Alamat
Wanita yang tinggal di tempat terpencil mungkin
memilih metode yang tidak mengharuskan mereka
berkonsultasi secara teratur dengan petugas keluarsga
berencana (Handayani, 2010).
b) Keluhan utama
Keluhan utama pada ibu pascasalin menurut Saifuddin
(2013), adalah:
(1) Usia 20-35 tahun ingin menjarangkan kehamilan.
(2) Usia>35 tahun tidak ingin hamil lagi.
c) Riwayat kesehatan
Untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas wanita
penderita penyakit jantung dalam kehamilan, persalinan,
dan nifas, perlu diperlukan konseling prakonsepsi dengan
memperhatikan resiko masing-masing penyakit. Pasien
dengan kelainan jantung derajat 3 dan 4 sebaiknya tidak
hamil dan dapat memilih cara kontrasepsi AKDR,
tubektomi atau vasektomi pada suami (Saifuddin, 2010).
d) Riwayat Kebidanan
(1) Haid
Meskipun beberapa metode KB mengandung risiko,
menggunakan kontrasepsi lebih aman, terutama apabila
ibu sudah haid lagi (Saifuddin, 2010).Wanita dengan
durasi menstruasi lebih dari 6 hari memerlukan pil KB
dengan efek estrogen yang rendah (Manuaba, 2010).
(2) Riwayat Kehamilan, Persalinan dan Nifas yang Lalu
Pasien yang tiga bulan terakhir sedang mengalami atau
sering menderita abortus septik tidak boleh
menggunakan kontraepsi IUD (Saifuddin, 2010).
270
(3) Riwayat KB
Riwayat kontrasepsi diperlukan karena kontrasepsi
hormonal dapat memengaruhi EDD, ketika seorang
menghabiskan pil berisi hormon dalam kaplet
kontrasepsi oral, periode menstruasi yang selanjutnya
akan dialami disebut “withdrawal bleed” (Roumali,
2011).
e) Pola kebiasaan sehari-hari
(1) Nutrisi
DMPA merangsang pusat pengendali nafsu makan di
hipotalamus, yang menyebabkan akseptor makan lebih
banyak dari biasanya (Hartanto, 2009).
(2) Eliminasi
Dilatasi ureter oleh pengaruh progestin, sehingga
timbul statis dan berkurangnya waktu pengosongan
kandung kencing karena relaksasi otot (Hartanto,
2009).
(3) Istirahat/tidur
Gangguan tidur yang dialami ibu akseptor KB suntik
sering disebabkan karena efek samping dari KB suntik
tersebut (mual, pusing, sakit kepala) (Saifuddin, 2010).
(4) Kehidupan seksual
Pola seksual merupakan faktor penting untuk
menentukan metode yang cocok selama fase tertentu
dalam kehidupan reproduksinya.(Saifudin, 2010).
(5) Riwayat Ketergantungan
Merokok terbukti menyebabkan efek sinergistik dengan
pil oral dalam menambah risiko terjadinya miokard
infark, stroke dan keadaan trombo-embolik (Hartanto,
2009).
271
2) Data Obyektif
a) Pemeriksaan umum
(1) Tanda-tanda vital
Suntikan progestin dan implan dapat digunakan untuk
wanita yang memiliki tekanan darah < 180/110 mmHg
.Pil dapat menyebabkan sedikit peningkatan tekanan
darah pada sebagian besar pengguna(Saifuddin, 2010).
(2) Pemeriksaan antropometri
Berat badan
Umumnya pertambahan berat badan tidak terlalu besar,
bervariasi antara kurang dari 1 kg sampai 5 kg dalam
tahun pertama.Penyebab pertambahan berat badan tidak
jelas.Tampaknya terjadi karena bertambahnya lemak
tubuh (Hartanto, 2009).
b) Pemeriksaan fisik
(1) Muka
Timbul hirsutisme (tumbuh rambut/bulu berlebihan di
daerah muka) pada penggunaan kontrasepsi progestin,
tetapi sangat jarang terjadi (Saifuddin, 2010).
(2) Mata
Kehilangan penglihatan atau pandangan kabur
merupakan peringatan khusus untuk pemakai pil
progestin (Saifuddin, 2010). Akibat terjadi perdarahan
hebat memungkinkan terjadinya anemia (Saifuddin,
2010).
(3) Payudara
Kontrasepsi suntikan tidak menambah risiko terjadinya
karsinoma seperti kasinoma payudara atau serviks,
namun progesteron termasuk DMPA, digunakan untuk
mengobati karsinoma endometrium (Hartanto, 2015).
Keterbatasan pada penggunaan KB progestin dan
272
implant akan timbul nyeri pada payudara (Saifuddin,
2010). Terdapat benjolan/kanker payudara atau riwayat
kanker payudara tidak boleh menggunakan implant
(Saifuddin, 2010).
(4) Abdomen
Peringatan khusus bagi pengguna implant bila disertai
nyeri perut bagian bawah yang hebat kemungkinan
terjadi kehamilan ektopik (Saifuddin, 2010).
(5) Genetalia
DMPA lebih sering menyebabkan perdarahan,
perdarahan bercak dan amenore (Hartanto, 2015).
Ibu dengan varises di vulva dapat menggunakan AKDR
(Saifuddin, 2010). Efek samping yang umum terjadi
dari penggunaan AKDR diantaranya mengalami haid
yang lebih lama dan banyak, perdarahan (spotting)
antar menstruasi, dan komplikasi lain dapat terjadi
perdarahan hebat pada waktu haid (Saifuddin, 2010).
(6) Ekstremitas
Pada pengguna implant, luka bekas insisi mengeluarkan
darah atau nanah disertai dengan rasa nyeri pada lengan
(Saifuddin, 2010).Ibu dengan varises di tungkai dapat
menggunakan AKDR (Saifuddin, 2010).
b. Menyusun Diagnosa
Pada langkah ini bidan mengidentifikasi masalah atau diagnosa
potensial berdasarkan rangkaian masalah atau diagnosa yang sudah
diidentifikasi.Langkah ini membutuhkan antisipasi bila
memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengawasi pasien
bidan bersiap-siap bila masalah potensial benar-benar terjadi.
Mengantisipasi perlunya tindakan segera oleh bidan dan/dokter
untuk konsultasi atau ditangani bersama dengan anggota tim
kesehatan lain (Walyani, 2015).
273
c. Merencanakan Asuhan kebidanan
Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang
sudah teridentifikasi dari kondisi/masalah klien, tapi juga dari
kerangka pedoman antisipasi terhadap klien tersebut, apakah
kebutuhan perlu konseling, penyuluhan dan apakah pasien perlu
dirujuk karena ada masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah
kesehatan lain. Pada langkah ini tugas bidan adalah merumuskan
rencana asuhan sesuai dengan hasil pembahasan rencana bersama
klien dan keluarga, kemudian membuat kesepakatan bersama
sebelum melaksanakannya (Walyani, 2015).
d. Melaksanakan asuhan kebidanan
Pada langkah ini melaksanakan asuhan yang komperhensif yang
telah dibuat dapat dilaksanakan secara efisien seluruhnya oleh bidan
atau dokter atau tim kesehatan lain (Walyani, 2015).
e. Evaluasi
Melakukan evaluasi hasil dari asuhan yang telah diberikan meliputi
pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah
terpenuhi sesuai dengan diagnosa/masalah (Walyani, 2015).
f. Pendokumentasian
Model dokumentasi yang digunakan dalam asuhan kebidanan yaitu
dalam bentuk catatan perkembangan karena bentuk asuhan yang
diberikan berkesinambungan dan menggunakan proses yang terus
menerus dengan menggunakan subjektif, objektif, analisis, dan
penatalaksanaan (SOAP) yang merupakan salah satu metode
pendokumentasian.
1) S = Subjektif
Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data
klien melalui anamnesis antara lain tanggal, tahun, waktu,
biodata, riwayat, termasuk kondisi klien. Catatan data spesifik
atau fokus. Tanda dan gejala subjektif yang didapatkan dari
hasil bertanya pada klien, suami dan keluarga. Catatan ini
274
berhubungan dengan masalah sudut pandang klien. Ekspresi
klien mengenai kekhawatiran dan keluhannya dicatat sebagai
kutipan langsung atau ringkasan yang berhubungan dengan
diagnosa.
2) O = Objektif
Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data
klien melalui pengamatan dan terukur, pemeriksaan fisik klien
didapatkan melalui inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi,
termasuk data penunjang. Data ini memberikan bukti gejala
klinis klien dan fakta yang berhubungan dengan diagnosa.
3) A = Analisis
Menggambarkan pendokumentasian hasil analisis, diagnosis,
dan masalah kebidanan.
4) P = Penatalaksanaan
Mencatat seluruh perencanaan dan penatalaksanaan yang telah
dilakukan, misalnya tindakan antisipatif, tindakan segera,
tindakan secara komprehensif, penyuluhan, dukungan,
kolaborasi, evaluasi/follow up dan rujukan. Dokumentasi
menunjukkan perencanaan yang tepat (Astuti dkk, 2017).
275
BAB III
TINJAUAN KASUS
A. Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil
1. Kunjungan ANC I
Tanggal Pengkajian : 11 April 2020
Waktu Pengkajian : Pukul 09.30 WIB
Tempat Pengkajian : PMB Siti Rohmani, S.ST
a. Data Subyektif
1) Identitas
Nama : Ny. T Nama Suami : Tn. S
Umur : 25 Tahun Umur : 30 Tahun
Agama : Islam Agama : Islam
Suku : Jawa Suku : Jawa
Pendidikan : SMA Pendidikan : SMU
Pekerjaan : IRT Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Segulung, Kec. Dagangan, Kab. Madiun
2) Keluhan Utama
Ibu mengatakan hamil anak Pertama, umur kehamilan 9 bulan, ingin
periksa hamil. Ibu mengatakan tidak ada keluhan yang dirasakan
sekarang
3) Riwayat Kesehatan
a) Riwayat Kesehatan Sekarang
Ibu mengatakan tidak sedang menderita penyakit dengan gejala
batuk lama, BB menurun, hilang nafsu makan, berkeringat malam
hari (TBC), banyak makan, banyak minum, sering kencing (DM),
nyeri perut sebelah kanan, kuning pada kulit/anggota badan
(hepatitis). Berkeringat berlebihan di telapak tangan dan jantung
berdebar-debar (jantung) dan tekanan darah tinggi (hipertensi),
tidak pernah mengalami sesak nafas (asma), tidak mempunyai
penyakit dengan gejala daya tahan tubuh menurun, mudah jatuh
276
sakit (HIV/AIDS), mengalami/merasa lemah, letih, lesu, lunglai,
lemas (anemia). Tidak pernah keputihan yang gatal dan berbau
(PMS).
b) Riwayat Penyakit Dahulu
Ibu mengatakan tidak pernah MRS dan menjalani operasi apapun
serta tidak pernah menderita penyakit dengan gejala batuk lama,
BB menurun, hilang nafsu makan, berkeringat malam hari (TBC),
banyak makan, banyak minum, sering kencing (DM), nyeri perut
sebelah kanan, kuning pada kulit/anggota badan (hepatitis).
Berkeringat berlebihan di telapak tangan dan jantung berdebar-
debar (jantung) dan tekanan darah tinggi (hipertensi), tidak
pernah mengalami sesak nafas (asma), tidak mempunyai penyakit
dengan gejala daya tahan tubuh menurun, mudah jatuh sakit
(HIV/AIDS), mengalami/merasa lemah, letih, lesu, lunglai, lemas
(anemia). Tidak pernah keputihan yang gatal dan berbau (PMS).
c) Riwayat kesehatan Keluarga
Ibu mengatakan dalam keluarga ibu maupun suami tidak ada yang
menderita penyakit dengan gejala batuk lama, BB menurun,
hilang nafsu makan, berkeringat malam hari (TBC), banyak
makan, banyak minum, sering kencing (DM), nyeri perut sebelah
kanan, kuning pada kulit/anggota badan (hepatitis). Berkeringat
berlebihan di telapak tangan dan jantung berdebar-debar (jantung)
dan tekanan darah tinggi (hipertensi), tidak pernah mengalami
sesak nafas berbunyi (asma), tidak mempunyai penyakit dengan
gejala daya tahan menurun, mudah jatuh sakit (HIV/AIDS),
mengalami/merasa lemah, letih, lesu, lunglai, lemas (anemia),
serta tidak memiliki riwayat kehamilan kembar.
4) Riwayat Pernikahan
Umur Menikah : 24 Tahun
Lama Menikah : 1 Tahun
Pernikahan ke : 1
277
Status Pernikahan : Sah
5) Riwayat Kebidanan
a) Haid
Menarche : 13 tahun
Siklus : 29 hari
Lama : 7-8 hari
Warna : merah segar
Sifat darah : encer dan sedikit kental
Jumlah : 2-3x ganti pembalut
Disminorhea : nyeri hari pertama haid
Flour albus : tidak ada
Bau : amis
HPHT : 10-7-2019
b) Riwayat kehamilan, persalinan, nifas yang lalu
Kehamilan Persalinan Anak Nifas
K
e
U
K
Penyu
lit
Tem
pat
Penol
ong
Jenis
Persalina
n
J
K
BB
Lahir
Umur
Anak
H
/
M
La
kta
si
Kom
plika
si
K
B
1 H A M I L I N I
c) Riwayat Keluarga berencana
Ibu belum pernah menggunakan alat kontrasepsi apapun
sebelumnya.
d) Kehamilan sekarang
(1) ANC pertama : 5 minggu
(2) Kunjungan ANC
(a) Trimester I
Periksa : 2 x
Tempat : PMB
Oleh : Bidan
Keluhan : Pusing, mual
Terapi : Mediamer 2x1, Arkavit 1x1
278
Penyuluhan : Makan sedikit tapi sering, kebutuhan dasar
ibu hamil
(b) Trimester II
Periksa : 4 x
Tempat : PMB dan Puskesmas
Oleh : Bidan
Keluhan : Batuk pilek, susah tidur
Terapi : Etabion 1x1, Licokalk 1x1, Tera F
Penyuluhan : Istirahat, ANC terpadu, gizi seimbang,
jalan pagi, tanda bahaya kehamilan
(c) Trimester III
Periksa : 5 x
Tempat : PMB
Oleh : Bidan
Keluhan : Sering Kencing
Terapi : Arkavit 1x1, Etabion 1x1
Penyuluhan : Senam hamil, persiapan persalinan, tanda-
tanda persalinan
Status Imunisasi TT : T5 Lengkap
Gerak janin : mulai terasa sejak usia kehamilan 4 bulan,
hingga saat ini gerakan janin dirasakan aktif.
6) Pola kebiasaan sehari-hari
a) Nutrisi
(1) Sebelum hamil : Makan teratur 3x sehari dengan komposisi
nasi, sayur, lauk. Minum air putih 7-8
gelas/hari
(2) Selama hamil : Makan teratur 3-4x sehari, dengan
komposisi nasi, sayur, lauk, tidak ada
pantangan makanan. Minum air putih 8-9
gelas/hari ditambah minum susu hamil
1x/hari
279
b) Eliminasi
(1) Sebelum hamil : BAB teratur 1x sehari, konsistensi lunak,
warna kuning, tidak ada keluhan BAB.
BAK 5-6 kali sehari, warna kuning jernih,
tidak ada keluhan BAK.
(2) Selama hamil : BAB teratur 1 x sehari, konsistensi lunak,
warna kuning, tidak ada keluhan BAB.
BAK 7-9 kali sehari, urine warna kuning
jernih dan tidak ada keluhan saat BAK.
c) Istirahat
(1) Sebelum hamil : Tidur siang ± 1 jam, tidur malam ± 7-8 jam
(2) Selama hamil : Tidur siang ± 2 jam, tidur malam ± 7-8 jam
d) Aktivitas
(1) Sebelum hamil : Ibu melakukan pekerjaan rumah tangga
seperti memasak, mencuci, menyapu secara
mandiri
(2) Selama hamil : Ibu melakukan pekerjaan rumah tangga
seperti memasak, mencuci, menyapu
dibantu suami / keluarga
e) Personal Hygiene
(1) Sebelum hamil : Mandi 2 kali sehari, keramas 2 hari sekali,
gosok gigi 2x sehari, genetalia dibersihkan
setiap kali BAB dan BAK serta mengganti
pakaian setiap selesai mandi
(2) Selama hamil : Mandi 2 kali sehari, keramas 2 hari sekali,
gosok gigi 2x sehari, genetalia dibersihkan
setiap kali BAB dan BAK serta mengganti
pakaian setiap selesai mandi
f) Seksual
(1) Sebelum hamil : Ibu mengatakan melakukan hubungan
seksual seminggu 3-4x. Saat berhubungan
280
seksual ibu tidak ada keluhan, tidak
mengalami perdarahan
(2) Selama hamil :Ibu mengatakan melakukan hubungan
seksual kadang-kadang dan tidak ada
keluhan selama berhubungan
7) Riwayat Ketergantungan
Ibu mengatakan sebelum hamil dan selama hamil ibu dan suami
tidak ada riwayat ketergantungan terhadap suatu makanan tertentu,
obat-obatan, minuman beralkohol dan jamu-jamuan. Suami merokok
tapi menjauh dari istri saat merokok.
8) Latar belakang sosial budaya
Ibu tidak pernah melakukan pijat perut, minum jamu dan tidak ada
pantang terhadap makanan tertentu seperti telur, daging, ikan.
9) Psikososial dan spiritual
Ibu mengatakan bahwa ibu, suami dan keluarga sangat mendukung
atas kehamilannya. Pengambilan keputusan dari kedua belah pihak,
baik ibu maupun suami. Ibu berharap kehamilannya lancar dan ibu
berdoa agar diberi kesehatan dan keselamatan sampai proses
persalinan nanti.
b. Data Obyektif
1) Pemeriksaan umum
Keadaan umum : baik
Kesadaran : composmentis
2) HPL : 17-4-2020
3) Usia kehamilan : 39+1
minggu
4) Pemeriksaan Tanda-tanda vital
TD : 110/70 mmHg Suhu : 36,8oC
Nadi : 82 x/menit RR : 20 x/menit
5) Pemeriksaan antropometri
BB sebelum hamil : 58 kg
BB sekarang : 67 kg
281
Kenaikan BB : 9 kg
TB : 158 cm
LILA : 27 cm
IMT : Berat badan (kg)
Tinggi badan (m)2
: 58 (kg)
1.58 (m)2
: 58
2,49
: 23,2 (normal)
6) Pemeriksaan fisik
a) Kepala
Inspeksi : bersih, rambut hitam, penyebaran merata, tidak mudah
rontok, tidak ada luka.
Palpasi : Kepala tidak ada benjolan abnormal, tidak nyeri tekan.
b) Muka
Inspeksi :tidak sembab, tidak pucat
Palpasi : tidak odema
c) Mata
Inspeksi : simetris, bersih, konjungtiva merah muda, sklera putih
Palpasi :kelopak mata tidak oedema
d) Hidung
Inspeksi : simetris, tidak ada sekret dan, tidak ada pernafasan
cuping hidung, tidak ada polip
e) Telinga simetris
Inspeksi : simetris,tidak ada serumen.
f) Mulut dan Gigi
Inspeksi : simetris, mukosa bibir lembab, tidak ada stomatitis,
gusi tidak berdarah, dan tidak ada caries gigi.
g) Leher
Inspeksi : bersih
282
Palpasi : tidak ada bendungan vena jugularis tidak ada
pembesaran kelenjar tyroid dan kelenjar limfe
h) Dada
Inspeksi : simetris, pernafasan teratur dan tidak ada retraksi
dinding dada.
Auskultasi: paru-paru : tidak ada suara tambahan seperti wheezing
dan ronchi, bunyi jantung normal dan teratur
Perkusi : jantung pekak, paru-paru sonor
i) Payudara
Inspeksi : simetris, puting menonjol, hyperpigmentasi areola
Palpasi : tidak ada benjolan abnormal, tidak nyeri tekan,
kolostrum sudah keluar.
j) Aksila
Inspeksi : bersih
Palasi : tidak ada pembesaran kelenjar limfe, tidak ada nyeri
tekan
k) Abdomen
Inspeksi : simetris, pembesaran abdomen sesuai dengan usia
kehamilan, tidak ada bekas luka operasi, terdapat
lineanigra dan strie livida..
Palpasi :Leopold I
TFU 3 jari bawah prosessus xyphoideus, pada fundus
teraba bagian bulat, lunak, tidak melenting (bokong)
Leopold II
Pada perut sebelah kanan janin teraba bagian keras
memanjang seperti papan (punggung), Pada perut
bagian kiri teraba bagian terkecil janin (ekstremitas).
Leopold III
Pada bagian terendah teraba bagian bulat, keras
(kepala) tidak dapat digoyangkan (sudah masuk PAP)
Leopold IV
283
Kedua ujung jari tangan pemeriksa tidak saling
bertemu/kepala sudah masuk PAP (divergen)
Perlimaan = 4/5.
TFU Mc Donald = 30 cm.
TBJ (Jhonson Tausak) = (30-11) x 155 = 2.945 gram
Auskultasi: Detak jantung janin (+) 146 kali/menit
teratur,terdengar jelas. Punctum maksimum 3 jari kanan
bawah pusat.
l) Genetalia
Inspeksi : bersih, tidak ada flour albus, tidak ada perdarahan
pervaginam, tidak ada tanda-tanda PMS (condiloma
akuminata dan condiloma matalata), tidak odema dan
varises
Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar bartolini dan kelenjar
scene
m) Anus
Inspeksi : bersih, tidak ada hemoroid
n) Ekstremitas
Inspeksi :
(1) Atas : simetris, jari lengkap, tidak ada kelainan polidaktili
dan sindaktili, gerak aktif
(2) Bawah : simetris, jari lengkap, tidak varises, tidak ada
kelainan polidaktili dan sindaktili, gerrak aktif
Palpasi : Tidak oedem
Perkusi : Reflek Patella : kanan kiri + / +
5) Pemeriksaan Penunjang
Tanggal : 20 Desember 2019
Tempat : Puskesmas Dagangan
a) Golongan darah : B
b) Haemoglobin : 12,2 gr %
c) GDA : 114 mg/dl
284
d) HIV/AIDS : Non Reaktif
e) HBSAg : Non Reaktif
f) Protein urine : Negatif
6) Kartu Skor Puji Rochyati (KSPR)
Skor ibu pada ANC tanggal 11 April 2020 yaitu 2
c. Analisa
Ny.”T” G1P00000 usia kehamilan 39+1
, janin tunggal, hidup, presentasi
kepala, puka, intra uterin, keadaan umum ibu dan janin baik.
d. Penatalaksanaan Jam : 09.45 WIB
1) Memberitahu ibu berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa keadaan ibu
dan janin baik.
E/Ibu senang mengetahui hasil pemeriksaannya.
2) Menganjurkan ibu untuk menambah porsi makan karena
penambahan BB ibu masih kurang.
E/Ibu mengerti dan akan melakukan
3) Memberitahu ibu tanda bahaya kehamilan yaitu muntah terus dan tak
mau makan, demam tinggi, bengkak kaki, tangan, dan wajah atau
sakit kepala disertai kejang, janin dirasakan kurang bergerak
dibandingkan sebelumnya, perdarahan dari jalan lahir, air ketuban
keluar sebelum waktunya.
E/Ibu mengerti tanda bahaya kehamilan yang dijelaskan.
4) Menjelaskan kepada ibu dan keluarga persiapan persalinan yaitu :
a) Menanyakan kepada bidan dan dokter tanggal perkiraan
persalinan
b) Suami atau keluarga mendampingi ibu saat periksa kehamilan
c) Menyiapkan lebih dari 1 orang yang memiliki golongan darah
yang sama dan bersedia menjadi pendonor jika diperlukan
d) Mempersiapkan tabungan atau dana untuk biaya persalinan dan
biaya lainnya
e) Suami, keluarga dan masyarakat menyiapkan kendaraan jika
sewaktu-waktu diperlukan
285
f) Merencanakan melahirkan ditolong oleh dokter atau bidan di
fasilitas kesehatan
g) Memastikan ibu hamil dan keluarga menyepakati amanat
persalinan dalam stiker P4K dan sudah ditempelkan di depan
rumah ibu hamil
h) Menyiapkan KTP, Kartu Keluarga, Kartu Jaminan Kesehatan
Nasional dan keperluan lain untuk ibu dan bayi yang akan
dilahirkan
i) Mendaftarkan diri ke kantor BPJS Kesehatan setempat, atau
tanyakan ke petugas Puskesmas untuk mendapat kartu JKN
j) Merencanakan ikut Keluarga Berencana (KB) setelah bersalin.
Menanyakan kepada petugas kesehatan tentang cara ber-KB
E/Ibu ingin bersalin ditolong oleh bidan di tempat praktik mandiri
bidan, menggunakan transportasi sendiri, biaya sudah dikumpulkan,
pengambil keputusan adalah suami, suami/ keluarga sebagai
pendamping dan pendonor darah adalah suami
5) Menjelaskan kepada ibu tentang tanda bahaya persalinan yaitu :
perdarahan lewat jalan lahir, tali pusar atau tangan bayi keluar dari
jalan lahir, ibu mengalami kejang, ibu tidak kuat mengejan, air
ketuban keruh dan berbau, ibu gelisah atau mengalami kesakitan
yang hebat
E/Ibu mengerti tanda bahaya persalinan
6) Menjelaskan kepada ibu tanda-tanda persalinan yaitu :
a) Perut mulas-mulas yang teratur, timbulnya semakin sering dan
semakin lama
b) Keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir atau keluar cairan
ketuban dari jalan lahir
E/Ibu mengerti tanda-tanda persalinan
7) Memberi ibu terapi obat peroral yaitu : Arkavit 1x1 dan Etabion 1x1
E/Ibu bersedia minum obat
286
8) Memberitahu ibu untuk kunjungan ulang satu minggu lagi yaitu
tanggal 17 April 2020 atau sewaktu-waktu jika ada keluhan.
E/Ibu bersedia periksa kembali 1 minggu lagi atau sewaktu-waktu
jika ada keluhan
KARISMA HAYU ISLAMI
B. Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin
1. Kala I Fase Aktif
Tanggal : 15 April 2020 Pukul : 12.00 WIB
a. Data Subyektif
Ibu mengatakan merasakan kenceng-kenceng, mules tidak terlalu sering
mulai tanggal 15 April 2020 pukul 08.00 WIB, setelah itu ibu merasa
kenceng-kenceng dan mules semakin sering mulai pukul 10.30 WIB,
kemudian ibu sampai di PMB pukul 12.00 WIB untuk memeriksakan
kehamilannya. Ibu terakhir BAB ± pukul 05.00 WIB, BAK terakhir ± 5
menit sebelum dilakukan pemeriksaan. Ibu terakhir makan ± 1 jam
yang lalu.
b. Data Obyektif
1) Pemeriksaan Umum
Keadaan umum : baik
Kesadaran : composmentis
BB sekarang : 67 kg
TD : 110/70 mmHg Suhu : 36,7 ° C
Nadi : 82 x/menit RR : 20x/menit
Palpasi : Leopold I
TFU 3 jari bawah px, pada fundus teraba bagian
bulat, lunak, tidak melenting (bokong).
Leopold II
Pada perut bagian kanan teraba bagian keras
memanjang seperti papan (punggung). Pada perut
287
bagian kiri teraba bagian terkecil janin
(ekstremitas).
Leopold III
Pada bagian terendah teraba bagian bulat, keras
(kepala) tidak dapat digoyangkan (sudah masuk
PAP).
Leopold IV
Kedua ujung jari tangan pemeriksa tidak saling
bertemu/kepala sudah masuk PAP (divergen)
Perlimaan : 3/5
TBJ : (30-11)x155 = 2.945 gram
His : 3x dalam 10 menit, lamanya 40 detik
Auskultasi : DJJ 147 kali/menit
2) Pemeriksaan dalam
Tanggal : 15 April 2020
Pukul : 12.00 WIB
VT pembukaan Ø 4 cm, tidak ada tumor, effacement 50%, ketuban
(+), presentasi kepala, Hodge II, UUK belum teraba.
c. Analisa
Ny.”T” G1P00000 , usia kehamilan 39+5
, inpartu kala 1 fase aktif, janin
tunggal, hidup, intrauterin, presentasi kepala, jalan lahir normal,
keadaan ibu dan janin baik.
d. Penatalaksanaan Jam : 12.00 WIB
1) Memberitahukan hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga, bahwa
kondisi ibu dan janin baik, ibu memasuki proses persalinan, jalan
lahir sudah mulai membuka.
E/Ibu dan keluarga memahami
2) Meminta suami atau keluarga untuk mendampingi ibu menghadapi
proses persalinan.
E/Ibu ditemani oleh suami dan keluarga
288
3) Menganjurkan ibu untuk melakukan teknik relaksasi saat ada his
yaitu dengan mengambil napas dalam dari hidung dan
mengeluarkannya dari mulut.
E/Ibu bisa mempraktekkan teknik relaksasi saat ada his
4) Menganjurkan ibu untuk jalan-jalan di sekitar tempat pemeriksaan.
E/Ibu jalan-jalan di sekitar tempat pemeriksaan
5) Menganjurkan ibu untuk miring kiri saat berbaring.
E/Ibu bersedia tidur miring kiri
6) Menganjurkan keluarga untuk memberikan makan dan minum pada
ibu saat tidak ada His sebagai nutrisi ibu untuk persiapan persalinan
pada saat mengejan.
E/Ibu bersedia makan dan minum
7) Menganjurkan ibu untuk tidak menahan BAK dan tidak perlu takut
BAB. Apabila ada rangsangan hendaknya ibu BAB supaya tidak
mengganggu kemajuan proses persalinan.
E/Ibu mengatakan tidak akan menahan BAK atau BAB
8) Meminta ibu untuk tidak mengejan dulu sebelum pembukaan
lengkap.
E/Ibu mengatakan bersedia untuk tidak mengejan sebelum
pembukaan lengkap
9) Melakukan observasi persalinan, his, DJJ dan nadi diperiksa tiap 30
menit, suhu dan urine tiap 2 jam, tekanan darah dan pemeriksaan
dalam setiap 4 jam atau jika ada indikasi.
2. Kala II
Tanggal : 15 April 2020 Pukul : 15.30 WIB
a. Data Subyektif
Ibu mengatakan kenceng-kenceng semakin sering dan semakin sakit.
Ibu merasakan adanya dorongan untuk mengejan seperti ingin BAB
yang tidak dapat ditahan.
289
b. Data obyektif
1) Ibu tampak kesakitan
2) Perineum menonjol, vulva dan anus membuka, terdapat pengeluaran
darah dan cairan dari jalan lahir
3) Penurunan kepala 1/5 bagian
4) His : 4 kali/10 menit, lamanya 45-50 detik
5) DJJ 146 x/menit
6) Pemeriksaan dalam :
VT : Pembukaan 10 cm, effacement 100%, ketuban (-) jernih, Hodge
III, UUK kanan depan, tidak ada molase, tidak ada tali pusat
disamping kepala, tidak ada bagian kecil disamping kepala.
c. Analisa
G1P00000 usia kehamilan 39+5
, inpartu kala II, keadaan ibu dan janin
baik.
d. Penatalaksanaan Jam : 15.30 WIB
1) Mendengar dan melihat tanda gejala kala II. Tanda gejala kala II
yaitu ibu merasakan ada dorongan ingin meneran, tekanan pada
anus, dan terlihat kondisi vulva yang membuka dan perineum yang
menonjol.
E/Sudah terdapat tanda gejala kala II
2) Memastikan perlengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan
esensial untuk menolong persalinan dan menatalaksana komplikasi
ibu dan bayi baru lahir.
E/Peralatan sudah disiapkan
3) Memakai celemek plastik/APD.
E/Celemek sudah dipakai
4) Melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai di
bawah siku, cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir dan
kemudian keringkan dengan tissue atau handuk yang bersih dan
kering.
290
E/Perhiasan sudah disimpan dan sudah mencuci tangan dengan
bersih
5) Memakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan
untuk pemeriksaan dalam.
E/sarung tangan telah dipakai
6) Masukkan oksitosin ke dalam spuit (gunakan tangan yang
menggunakan sarung tangan DTT dan steril dan pastikan tidak
terjadi kontaminasi pada alat suntik).
E/Oksitosin telah dimasukkan dalam spuit
7) Melakukan vulva hygiene dengan menggunakan kapas atau kasa
yang dibasahi air DTT.
E/Vulva dan perineum sudah bersih
8) Melakukan periksa dalam dengan hati-hati untuk memastikan
pembukaan sudah lengkap.
E/Pembukaan lengkap 10 cm, ketuban (-) jernih
9) Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan
yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%,
kemudian lepaskan dan rendam dalam keadaan terbalik dalam
larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Cuci kedua tangan setelah
sarung tangan dilepaskan.
E/Sudah dilakukan dekontaminasi dan sudah mencuci tangan
dengan bersih
10) Memeriksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi/saat
relaksasi uterus untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal
(120 – 160 x/menit).
E/DJJ normal 146x/menit
11) Memberitahukan bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan
janin baik dan bantu ibu dalam menemukan posisi yang nyaman
dan sesuai dengan keinginannya.
E/Ibu memilih posisi setengah duduk
291
12) Meminta keluarga untuk membantu menyiapkan posisi meneran
bila ada rasa ingin meneran dan terjadi kontraksi yang kuat, bantu
ibu ke posisi setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan
pastikan ibu merasa nyaman.
E/Keluarga bersedia membantu ibu memilih posisi yang nyaman
13) Melaksanakan pimpinan meneran pada saat ibu merasa ada
dorongan kuat untuk meneran atau timbul kontraksi yang kuat.
E/Ibu mengerti penjelasan dan melakukan arahan meneran yang
benar
14) Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil
posisi yang nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk
meneran dalam 60 menit.
E/Ibu memilih posisi setengah duduk
15) Meletakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut
bawah ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter
5-6 cm.
E/Handuk telah diletakkan diperut ibu
16) Meletakkan kain yang bersih dan kering yang dilipat 1/3 bagian di
bawah bokong ibu.
E/Kain sudah diletakkan dibawah bokong ibu
17) Membuka tutup partus set dan memeriksa kembali kelengkapan
alat dan bahan.
E/Partus set sudah lengkap dan siap digunakan
18) Memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan.
E/Sarung tangan sudah terpakai dengan benar
19) Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5 – 6 cm membuka
vulva maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi
kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan belakang kepala
bayi untuk mempertahankan posisi fleksi dan membantu lahirnya
kepala. Anjurkan ibu untuk meneran secara efektif atau bernapas
cepat dan dangkal.
292
E/Tangan kanan melindungi perineum, tangan kiri menahan kepala
bayi
20) Memeriksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil
tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi, dan segera lanjutkan
proses kelahiran.
E/Tidak ada lilitan tali pusat
21) Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi
luar secara spontan.
E/Kepala bayi mengalami putar paksi luar
22) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara
biparietal. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan
lembut gerakkan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu
depan muncul di bawah arkus pubis dan kemudian gerakan arah
atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang.
E/Bahu depan dan bahu belakang lahir
23) Setelah kedua bahu lahir, geser tangan bawah untuk kepala dan
bahu. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang
lengan dan siku sebelah atas.
E/Tubuh dan lengan bayi lahir
24) Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut
ke punggung, bokong tungkai dan kaki. Pegang kedua mata kaki
masukkan telunjuk diantara kaki dan pegang masing-masing mata
kaki dengan ibu jari dan jari-jari lainnya.
E/Seluruh badan bayi lahir
25) Melakukan penilaian selintas bayi baru lahir.
E/Jam 16.00 WIB, bayi cukup bulan, menangis kuat, gerak aktif
26) Mengeringkan bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh
lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks. Ganti
handuk basah dengan handuk/kain yang kering. Biarkan bayi di
atas perut ibu.
E/Bayi berada di atas perut ibu
293
3. Kala III
Tanggal: 15 April 2020 Pukul: 16.00 WIB
a. Data Subyektif
Ibu mengatakan lega karena bayinya sudah lahir dan ibu mengatakan
perutnya masih mules.
b. Data obyektif
1) Keadaan umum : Baik
2) Kesadaran : Composmentis
3) Kandung kemih : Kosong
4) Kontraksi uterus : baik
5) TFU : Setinggi pusat, uterus membulat globuler
6) Tali pusat nampak memanjang di depan vulva
7) Darah keluar tiba-tiba
c. Analisa
P10001 inpartu kala III
d. Penatalaksanaan Jam : 16.00 WIB
27) Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada bayi dalam
uterus.
E/Ibu hamil tunggal
28) Memberitahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin.
E/Ibu bersedia disuntik oksitosin
29) Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin 10 unit
IM (intamuskuler) di 1/3 paha atas bagian distal lateral lakukan
aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin.
E/Oksitosin telah disuntikkan, tidak ada perdarahan
30) Dalam waktu 2 menit setelah bayi lahir, jepit tali pusat dengan
klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Dorong isi tali pusat ke arah
distal (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem
pertama.
E/Tali pusat sudah dijepit dengan klem
31) Melakukan pemotongan dan pengikatan tali pusat.
294
E/Tali pusat sudah dipotong dan diikat
32) Meletakkan bayi tengkurap di dada ibu secara skin to skin / kontak
kulit ibu ke kulit bayi serta menyelimuti ibu dan bayi dengan kain
hangat dan pasang topi di kepala bayi, biarkan selama 1 jam untuk
IMD
E/Bayi berada di dada Ibu untuk IMD
33) Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari
vulva.
E/Klem berada di depan vulva sekitar 5 cm
34) Meletakkan satu tangan di atas kain pada perut bawah ibu, di atas
simfisis, untuk mendeteksi kontraksi. Tangan lain memegang klem
untuk menegangkan tali pusat.
E/Tangan kiri berada di tepi atas simfisis ibu
35) Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah
sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang-atas
(dorso-kranial) secara hati-hati. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-
40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul
kontraksi berikutnya dan ulangi prosedur di atas.
E/Penegangan tali pusat terkendali dilakukan saat uterus
berkontraksi
36) Melakukan penegangan dan dorongan dorso-kranial hingga
plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong
menegangkan tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke
arah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorso-
kranial).
E/Telah dilakukan penegangan tali pusat terkendali kembali
37) Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan
kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban
terpilin kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah
yang telah disediakan.
E/Plasenta lahir
295
38) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase
uterus, letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase
dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus
berkontraksi.
E/Masase sudah dilakukan dan uterus teraba keras
39) Mengevaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum.
E/Terdapat ruptur pada perineum derajat 2 pada mukosa vagina,
komisura posterior, kulit perineum dan otot perineum, dilakukan
penjahitan oleh bidan.
40) Memeriksa kedua sisi plasenta baik bagian ibu maupun bayi dan
pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Masukkan plasenta ke
dalam kantung plastik atau tempat khusus.
E/Plasenta lahir spontan jam 16.05 WIB, pada sisi maternal selaput
ketuban utuh, kotiledon 20 (lengkap), diameter 20 cm, tebal 2 cm,
sisi fetal tidak ada pembuluh darah yang putus, panjang tali pusat ±
40 cm.
41) Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi
perdarahan pervaginam.
E/Uterus berkontraksi dengan baik, uterus teraba keras, tidak
terjadi perdarahan pervaginam.
4. Kala IV
Tanggal: 15 April 2020 Pukul: 16.20 WIB
a. Data Subyektif
Ibu mengatakan lega bayi dan ari-arinya telah lahir, ibu merasa lelah
dan ingin istirahat.
b. Data Obyektif
1) Pemeriksaan Umum
Keadaan Umum : Baik
Kesadaran : Composmentis
TD : 100/70 mmHg Suhu : 36,7 °C
296
Nadi : 80 x/menit RR : 20 x/menit
2 Payudara : puting menonjol, hyperpigmentasi areola lunak, tidak ada
benjolan abnormal, tidak nyeri tekan, kolostrum sudah keluar.
3 TFU 2 jari dibawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih
kosong.
4 Genetalia : Terdapat luka jahitan, perdarahan pervaginam normal, ±
20 cc.
c. Analisa
P10001 inpartu kala IV
d. Penatalaksanaan Jam : 16.30 WIB
42) Memastikan kandung kemih kosong, jika penuh lakukan
kateterisasi.
E/Kandung kemih kosong
43) Memasukkan tangan yang masih memakai sarung tangan kedalam
larutan klorin 0,5 %, besihkan noda darah dan cairan tubuh dan
bilas di air DTT tanpa melepas sarung tangan kemudian keringkan
dengan tissue atau handuk pribadi yang bersih dan kering.
E/Sarung tangan sudah dibersihkan
44) Mengajarkan ibu/keluarga cara melakukan masase uterus dan
menilai kontraksi.
E/Ibu mengerti dan bisa melakukan massase
45) Memeriksa nadi ibu dan pastikan keadaan umum ibu baik
E/Nadi ibu normal dan keadaannya baik
46) Mengevaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah.
E/Jumlah kehilangan darah ± 200 cc
47) Memantau tanda-tanda bahaya pada bayi setiap 15 menit. Pastikan
bahwa bayi bernafas dengan baik (40-60 kali/menit) serta suhu
tubuh normal (36,5-37,5 °C).
E/Keadaan bayi baik
297
48) Membersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Bersihkan sisa
cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai pakaian yang
bersih dan kering.
E/Ibu sudah bersih dari paparan darah dan cairan tubuh
49) Memastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI.
Anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dan makanan yang
diinginkannya.
E/Ibu merasa lebih nyaman dengan dukungan orang sekitar
50) Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin
0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas peralatan
setelah di dekontaminasi.
E/Peralatan sudah ditempatkan dalam larutan klorin 0,5%
51) Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah
yang sesuai.
E/Bahan yang terkontaminasi sudah dibuang dalam tempat sampah
medis
52) Mendekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%.
E/Tempat bersalin telah didekontaminasi dengan larutan klorin
0,5%
53) Menyelupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%,
balikkan bagian dalam ke luar dan rendam dalam larutan klorin
0,5% selama 10 menit. Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air
mengalir
E/Sarung tangan sduah dilepas secara terbalik dan tangan sudah
dicuci dengan bersih
54) Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir kemudian
keringkan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering.
E/Tangan telah dicuci dengan bersih
55) Pakai sarung tangan DTT untuk memberikan vitamin K1 (1mg)
pada bayi secara intramuskular (IM) di paha kiri bawah lateral dan
salep mata profilaksis dalam 1 jam pertama kelahiran.
298
E/Vitamin K1 dan salep mata telah diberikan
56) Melakukan pemeriksaan fisik lanjutan (setelah 1 jam kelahiran
bayi). Memastikan kondisi bayi tetap baik (pernapasan normal 40-
60 kali/menit dan temperatur tubuh normal 36,5-37,5°C) setiap 15
menit
E/Keadaan bayi baik
57) Memberikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan bawah
lateral setelah 1 jam pemberian vitamin K1. Letakan bayi dalam
jangkuan ibu agar sewaktu – waktu bisa disusukan
E/Imunisasi Hepatitis B sudah diberikan dan bayi berada di dekat
ibu
58) Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam
didalam larutan klorin 0,5 selama 10 menit.
E/Sarung tangan telah dilepaskan dalam keadaan terbalik
59) Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir kemudian
keringkan dengan tisu atau handuk yang bersih dan kering.
E/Tangan sudah bersih
60) Lengkapi Partograf.
E/Partograf telah dilengkapi
KARISMA HAYU ISLAMI
C. Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas
1. Kunjungan Nifas I (6 jam post partum)
Tanggal : 15 April 2020
Pukul : 22.30 WIB
Tempat : PMB Siti Rohmani, S.ST
a. Data Subyektif
Ibu mengatakan:
1) Perutnya masih terasa mulas.
2) Nyeri pada luka jahitan
299
3) Perdarahan sedikit sudah 1x ganti pembalut
4) Kolostrum sudah keluar sedikit dan ibu sudah memberikannya pada
bayinya
5) Sudah BAK sebanyak 2 kali, tidak ada keluhan. Ibu belum bisa BAB
6) Saat ini ibu sudah makan 1 porsi sedang dengan menu nasi putih,
sayur sop, tempe serta telur goreng dimakan sampai habis dan
minum 1 botol (600 ml) air mineral
7) Saat ini ibu sudah melakukan mobilisasi seperti miring kanan dan
kiri terlebih dahulu, kemudian duduk dan berangsur-angsur berdiri
dan berjalan.
b. Data Obyektif
1) Pemeriksaan Umum
a) Keadaan umum : Baik
b) Kesadaran : Composmentis
c) TD : 110/70 mmHg Suhu : 36,7°C,
Nadi : 83 x/menit RR : 20x/menit
2) Pemeriksaan Fisik
a) Kepala
Inspeksi : bersih, rambut hitam, penyebaran merata, tidak
mudah rontok, tidak ada luka.
Palpasi :Kepala tidak ada benjolan abnormal, tidak nyeri
tekan.
b) Muka
Inspeksi : tidak pucat
Palpasi : tidak odema
c) Mata
Inspeksi : simetris, bersih, konjungtiva merah muda, sklera
putih, pupil isokor, mengikuti reaksi cahaya.
Palpasi : kelopak mata tidak oedema
d) Hidung
300
Inspeksi : simetris, tidak ada sekret dan tidak ada pernafasan
cuping hidung, tidak ada polip
e) Telinga
Inspeksi : simetris, tidak ada serumen.
f) Mulut
Inspeksi : Simetris, bersih, mukosa bibir lembab, tidak pucat,
tidak ada stomatitis, lidah bersih, tidak ada perdarahan gusi, tidak
ada caries gigi.
g) Leher
Inspeksi : tidak ada bendungan vena jugularis, tidak ada
pembesaran kelenjar tyroid dan kelenjar limfe
h) Dada
Inspeksi : simetris tidak ada retraksi dinding dada.
Auskultasi : pernafasan teratur, tidak ada wheezing dan ronchi,
bunyi jantung normal dan teratur
Perkusi : jantung pekak, paru-paru sonor
i) Payudara
Inspeksi : simetris, bersih, puting menonjol hyperpigmentasi
areola
Palpasi : tidak ada benjolan abnormal, tidak nyeri tekan,
kolostrum sudah keluar.
j) Aksila
Inspeksi : bersih
Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar limfe, tidak ada
benjolan abnormal, tidak ada nyeri tekan
k) Abdomen
Inspeksi : simetris, tidak ada bekas luka operasi
Palpasi : TFU 2 jari dibawah pusat, kontraksi uterus keras,
kandung kemih kosong.
l) Genetalia
301
Inspeksi : terdapat luka jahitan, perdarahan pervaginam
normal, lochea rubra.
m) Anus
Inspeksi : tidak ada hemoroid
n) Ekstremitas
Inspeksi: simetris, jari lengkap, tidak ada varises
Palpasi: tidak oedem dan tidak varises
c. Analisa
Ny.”T” P10001 , 6 jam post partum, fisiologis
d. Penatalaksanaan Jam : 22.40 WIB
1) Menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa ibu dalam keadaan
sehat.
E/Ibu merasa lega dan senang
2) Menjelaskan penyebab timbulnya rasa mulas pada perut bahwa
mulas yang dirasakan merupakan kontraksi untuk pengembalian
rahim ke keadaan semula / involusi uteri dan untuk mencegah
perdarahan.
E/Ibu mengerti tentang penyebab mulas yang dirasakan dan dapat
menerima
3) Menjelaskan pada ibu mengenai lochea yaitu pengeluaran
cairan/secret yang berasal dari rahim melalui jalan lahir dan
merupakan hal yang normal. Hari 1-3 pascasalin lochea yang keluar
berwarna merah segar (lochea rubra), hari 3-7 pascasalin berwarna
merah kecoklatan (lochea sanguinolenta), hari 7-14 pascasalin
berwarna kekuningan (lochea serosa), lebih 14 hari pascasalin
berwarna putih (lochea alba). Dan memberitahu ibu untuk datang ke
PMB jika keluar cairan yang berbau.
E/Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan
4) Menjelaskan pada ibu kebutuhan dasar masa nifas dan perawatan
bayi baru lahir
E/Ibu mengerti dan mampu mengulangi penjelasan
302
5) Menjelaskan tentang ASI ekslusif yaitu bayi hanya diberikan ASI
selama 6 bulan tanpa makanan tambahan lain dan menjelaskan
manfaat ASI pada ibu yaitu membantu proses involusi/kembalinya
uterus ke bentuk semula dan mencegah perdarahan, manfaat pada
bayi yaitu mengandung antibodi, makanan yang mengandung cukup
gizi bagi bayi, dan akan membangun ikatan bounding attachment.
E/Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan bersedia untuk
memberikan ASI eksklusif
6) Menjelaskan pada ibu tanda bahaya pada masa nifas seperti
perdarahan lewat jalan lahir, keluar cairan berbau dari jalan lahir,
bengkak di wajah, tangan dan kaki, atau sakit kepala dan kejang-
kejang, demam lebih dari 2 hari, payudara bengkak merah disertai
rasa sakit, serta merasa sedih, murung dan menangis tanpa sebab.
E/Ibu mampu menyebutkan sebagian tanda-tanda bahaya pada masa
nifas.
7) Menganjurkan ibu untuk tidak tarak makanan dan menganjurkan ibu
untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, seperti
ikan laut, telur, tahu, tempe dan lainnya untuk mempercepat proses
penyembuhan luka jahitan perineum.
E/Ibu bersedia melakukannya.
8) Melakukan perawatan payudara ibu yaitu membersihkan puting ibu
dengan kapas dan baby oil lalu melakukan pijatan dan memberikan
kompres dengan air hangat dan air dingin.
E/Ibu bersedia dan sudah dilakukan
9) Memberikan KIE pada ibu untuk menjaga kebersihan diri dan area
genetalia, cebok dari depan kebelakang, dan sering mengganti
pembalut
E/Ibu mengerti dan bersedia melakukan
10) Mengingatkan ibu untuk meneruskan meminum obat yang telah
diberikan. (amoxicillin 3x1, fargetic 3x1, Hemobion 1x1, vit A 1x1)
E/Ibu bersedia minum obat
303
11) Menyepakati untuk kunjungan ulang pada tanggal 20 April 2020
atau sewaktu-waktu jika ada keluhan.
E/Ibu menyepakati
2. Kunjungan Nifas II (6 hari post partum)
Tanggal : 20 April 2020
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : PMB Siti Rohmani, S.ST
a. Data Subyektif
Ibu mengatakan:
1) Daerah luka jahitan masih terasa nyeri
2) Sudah BAB hari ke 2 setelah persalinan, BAK lancar 5-6 kali/hari
3) ASI lancar, disusukan pada bayinya, bayi menyusu kuat
4) Makan 3 kali sehari porsi sedang, komposisi nasi, sayur, lauk, buah
dan minum air putih 8-9 gelas sehari
5) Bisa beristirahat setiap bayi tidur dan setiap 2 jam bangun untuk
menyusui bayinya
6) Ibu melakukan aktifitas ringan seperti jalan-jalan disekitar rumah
dan merawat bayinya
b. Data Obyektif
1) Pemeriksaan Umum
a) Keadaan umum : Baik
b) Kesadaran : Composmentis
c) TD : 110/80 mmHg Suhu : 36,7°C,
Nadi : 82 x/menit RR : 21x/menit
2) Pemeriksaan Fisik
Payudara simetris, bersih, puting bersih, menonjol, hyperpigmentasi
areola dan papila, putting tidak lecet, tidak ada benjolan abnormal,
tidak nyeri tekan, ASI keluar, TFU pertengahan pusat dan simfisis,
kandung kemih kosong, genetalia bersih, terdapat luka jahitan
304
perineum agak kering, tidak ada tanda infeksi, perdarahan
pervaginam normal, lochea sanguinolenta, tidak ada haemoroid.
c. Analisa
Ny.”T” P10001 , postpartum hari ke 6, fisiologis
d. Penatalaksanaan Jam : 08.10 WIB
1) Menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa ibu dalam keadaan
sehat, proses involusi berjalan normal, laktasi lancar, pengeluaran
lochea normal.
E/Ibu lega mengetahui keadaannya
2) Menjelaskan pada ibu penyebab rasa nyeri pada daerah luka jahitan
disebabkan karena proses penyembuhan luka dan itu merupakan hal
yang normal dan dianjurkan untuk tetap menjaga kebersihan daerah
genetalia.
E/Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan
3) Mendiskusikan ulang tentang ASI eksklusif dan manfaatnya.
E/Ibu mampu menyebutkan manfaat ASI eksklusif dan berencana
memberikan ASI ekslusif pada bayinya
4) Menjelaskan pada ibu teknik menyusui yang benar.
E/Ibu bisa melakukan
5) Menyepakati kunjungan ulang pada tanggal 14 Mei 2020 atau
sewaktu-waktu bila ada keluhan.
E/Ibu menyepakati
3. Kunjungan Nifas III (30 Hari Post Partum)
Tanggal : 14 Mei 2020
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Rumah Ny.”T”
a. Data Subyektif
Ibu mengatakan:
1) Tidak ada keluhan
2) ASI lancar, sering menyusui dan bayi menyusu kuat.
305
3) Makan 3 kali sehari dengan porsi sedang, tidak ada pantangan
makanan
4) BAK 5-6 kali sehari, warna kuning jernih, tidak ada keluhan
selama BAK, BAB 1 kali sehari, tidak ada keluhan pada BAB
5) Tidur kurang lebih 6-7 jam pada malam hari dan tidur siang saat
bayinya tidur, bangun tiap 2 jam sekali untuk menyusui bayinya
dan saat bayinya menangis
6) Menjaga personal hygiene, cebok dari depan ke belakang setelah
BAK dan BAB
7) Tidak merasa berat menjalani masa nifasnya karena suami dan
ibunya selalu membantu merawat bayinya
8) Ibu belum melakukan hubungan seksual
b. Data Obyektif
1) Pemeriksaan Umum
Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis
TD : 110/80 mmHg Suhu : 36,6°C
Nadi : 80 x/menit RR : 20 x/menit
2) Pemeriksaan Fisik
Payudara simetris, bersih, tidak lecet, tidak ada bendungan ASI,
ASI keluar lancar, TFU tidak teraba, kandung kemih kosong,
genetalia bersih, loche alba, jahitan di perineum sudah kering dan
tidak ada infeksi.
c. Analisa
Ny.”T” P10001 postpartum hari ke 30, fisiologis
d. Penatalaksanaan Jam : 14.10 WIB
1) Menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa ibu dalam keadaan
sehat
E/Ibu terlihat lega dengan keadaannya
2) Memberikan KIE tentang pentingnya ASI Eksklusif selama 6 bulan
tanpa memberikan makanan tambahan lainnya.
E/Ibu mengerti dan bersedia memberikan ASI eksklusif
306
3) Mendiskusikan tentang KB yang dapat digunakan pada ibu
pascasalin dan ibu menyusui
E/Ibu ingin menggunakan KB suntik 3 bulan
KARISMA HAYU ISLAMI
D. Asuhan Kebidanan Pada Neonatus
1. Kunjungan Neonatus I (6 jam Post Partum)
Tanggal : 15 April 2020
Pukul : 22.00 WIB
Tempat : PMB Siti Rohmani, S.ST
a. Data Subyektif
1) Biodata
Nama : Bayi Ny. “T”
Tanggal Lahir : 15 April 2020, pukul 16.00 WIB
Umur : 6 jam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Anak ke : 1 (satu)
2) Keluhan utama
Ibu mengatakan melahirkan bayi normal pada tanggal 15 April 2020,
pukul 16.00 WIB, jenis kelamin laki-laki, bayi dalam keadaan sehat,
menyusu kuat, sudah BAB dan BAK, tidak ada keluhan apapun.
3) Riwayat Kesehatan
a) Riwayat kesehatan sekarang
Ibu mengatakan bayi sejak lahir sampai sekarang belum pernah
sakit
b) Riwayat kesehatan keluarga
Dalam keluarga ibu dan ayah tidak ada yang sedang atau pernah
mendita penyakit menahun dengan gejala sering sesak nafs, nyeri
dada dan berdebar (jantung), penyakit menurun dengan gejala
sering BAK, sering makan, minum (DM), tekanan darah tinggi,
307
penyakit menular dengan gejala batuk lama disertai dahak dan
darah, nafsu makan berkurang (TBC), dan penyakit IMS dan
HIV/AIDS.
4) Riwayat Kebidanan
a) Riwayat antenatal
Ibu mengatakan hamil yang pertama. Selama hamil ibu tidak ada
keluhan yang serius hanya mual-mual pada kehamilan muda, ibu
rutin periksa, mulai periksa saat usia kehamilan 1 bulan,
selanjutnya rutin tiap bulan, ibu periksa rutin sebanyak 11 kali.
Selama hamil mendapat tablet tambah darah, vitamin, kalk dan
diminum rutin. Juga mendapat penyuluhan tentang gizi ibu hamil,
personal hygiene, perawatan payudara, senam hamil, aktifitas ibu
hamil, tanda bahaya kehamilan, persiapan persalinan, tanda-tanda
persalinan. Ibu berusaha melaksanakan semua yang diberi tahu
bidan. Selama hamil ibu setiap hari berusaha makan-makanan
bergizi untuk perkembangan bayinya.
b) Riwayat natal
Ibu mengatakan telah melahirkan bayinya pada tanggal 15 April
2020 pukul 16.00 WIB. Bayi lahir spontan, AS = 8-9, menangis
kuat dan gerak aktif, jenis kelamin laki-laki, BB 3000 gram, PB
51 cm, tidak ada kelainan bawaan. Ibu mengatakan segera setelah
lahir bayi langsung dilakukan IMD selama 1 jam.
c) Riwayat postnatal
Ibu mengatakan bayinya setelah lahir dalam kondisi baik, bayi
lahir langsung menangis, IMD ± 1 jam, kolostrum ibu sudah
keluar, dan bayi langsung menyusu kuat. Bayi sudah BAK 3 kali,
warna kuning jernih dan bayi sudah BAB 1 kali warna kehitaman,
konsistensi lunak
5) Pola kebiasaan sehari-hari
a) Nutrisi
Bayi diberi ASI saja, frekuensi sering, setiap 2 jam sekali
308
b) Eliminasi
BAB 1 kali, konsistensi lunak, warna feses kehitaman. Bayi BAK
3 kali, warna kuning jernih.
c) Istirahat/ tidur
Bayi lebih banyak tidur, menangis ketika lapar, BAK dan BAB
d) Aktivitas
Bayi menangis kuat dan gerak aktif.
e) Personal hygiene
Bayi belum dimandikan, mengganti pakaian setiap basah dan
kotor, mengganti popok setiap BAK dan BAB
6) Latar belakang sosial budaya
Bayi dirawat dan tinggal dirumah bersama orang tua dan keluarga.
Dalam keluarga tidak ada kebiasaan memberikan makanan tambahan
pada bayi sebelum umur 6 bulan, ada kebiasaan brokohan, dan tidak
ada kebiasaan merawat tali pusat dengan ramuan tradisional.
7) Psikososial dan spiritual
Bayi tampak nyaman ketika dekat dengan ibunya. Ketika bayi
menangis bayi langsung diam bila digendong. Orang tua dan
keluarga sangat senang atas kelahiran bayinya.
8) Riwayat Imunisasi
Bayi sudah mendapatkan imunisasi Hb0 1 jam setelah penyuntikan
vitamin K1
b. Data Obyektif
1) Pemeriksaan Umum
a) Keadaan umum : Baik
b) Kesadaran : Composmentis.
c) TTV
N : 130x /menit S : 36,8ºC
R : 48x /menit
d) Pengukuran antropometri
BB : 3000 gram
309
PB : 51 cm
LK : 34 cm
LD : 32cm
LILA : 10 cm
2) Pemeriksaan fisik
a) Kepala
Inspeksi : Simetris, rambut warna hitam, penyebaran merata
Palpasi :Tidak ada benjolan abnormal, tidak ada molase,
tidak ada caput succadaneum, cephal hematoma,
dan hidrosepalus.
b) Mata
Inspeksi : Kedua mata simetris, konjungtiva merah muda,
sklera putih, tidak ikterus, tidak ada pengeluaran
sekret berlebih, tidak ada kelainan.
c) Hidung
Inspeksi :Bentuk simetris, tidak ada sekret pada hidung, tidak
ada pernapasan cuping hidung, septum lurus
ditengah.
d) Mulut
Inspeksi :Bibir kemerahan, tidak ada labio schisis, labio
palato schisis, dan labio palato genato schisis,
mukosa bibir lembab.
e) Telinga
Inspeksi :Simetris, tulang rawan dan elastisnya sudah
terbentuk dengan baik, tidak ada pengeluaran
sekret/serumen.
f) Leher
Inspeksi :Tidak ada kaku kuduk.
Palpasi :Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid dan kelenjar
limpa, tidak ada bendungan vena jugularis.
310
g) Dada
Inspeksi :Bentuk simetris, tidak ada retraksi dinding dada.
Auskultasi : Pernapasan teratur, tidak ada wheezing dan ronchi,
tidak ada kelainan irama jantung.
Perkusi : Jantung pekak, paru-paru sonor
h) Abdomen
Inspeksi :Dinding abdomen simetris, tali pusat masih basah,
tidak ada perdarahan pada tali pusat, tidak berbau
busuk, tidak ada pus dan tali pusat dibungkus
dengan kasa kering steril
Palpasi : Teraba lunak
Auskultasi : Suara bising usus normal.
Perkusi : tidak kembung
i) Genetalia
Inspeksi : Jenis kelamin laki-laki, testis sudah turun kedalam
skrotum, lubang uretra berada di ujung penis
j) Anus
Inspeksi : Terdapat lubang anus.
Palpasi : Anus berlubang.
k) Ektremitas
Inspeksi : Atas : simetris, normal, jumlah jari-jari lengkap,
tidak ada kelainan, gerak aktif
Bawah : simetris, normal, jumlah jari-jari lengkap,
tidak ada kelainan, gerak aktif.
l) Kulit
Inspeksi :Warna kemerahan, tidak pucat, kulit halus, lembut,
tidak ada pengelupasan kulit
Palpasi : turgor kulit baik
311
3) Pemeriksaan Reflek
a) Reflek glabela
Baik. Bayi berkedip saat bagian glabela (bagian dahi antara dua
alis mata) diketuk dengan jari telunjuk.
b) Reflek rooting
Baik. Saat ujung bibir bayi dirangsang menggunakan puting susu
ibu, bayi berusaha mencarinya.
c) Reflek sucking
Baik. Bayi sudah mampu menghisap puting dengan kuat.
d) Reflek swallowing
Baik. Bayi dapat menelan dengan baik.
e) Reflek tonic neck
Baik. Saat kepala bayi dimiringkan ke kiri dan lengan kirinya
meregang lurus sementara siku lengan kanannya melipat.
f) Reflek grassping
Baik. Saat jari pemeriksa diletakkan pada telapak tangan bayi,
bayi merespon dengan menggenggam jari tersebut.
g) Reflek morro
Baik. Saat dikagetkan, bayi bergerak seperti memeluk.
h) Reflek babinsky
Baik. Saat jari pemeriksa mengusap bagian bawah kaki bayi, jari
bayi akan membuka.
i) Reflek Stepping
Baik. Ketika bayi digendong berdiri kaki bayi akan menapak
seperti berjalan dan melangkah.
c. Analisa
Bayi Ny. “T” usia 6 jam, bayi baru lahir normal, cukup bulan, sesuai
masa kehamilan, keadaan umum baik
d. Penatalaksanaan Jam : 22.10 WIB
1) Menjelaskan kepada ibu hasil pemeriksaan bahwa keadaan bayinya
baik.
312
E/Ibu mengetahui keadaan bayinya dan merasa senang
2) Menjelaskan mengenai perawatan bayi sehari-hari meliputi menjaga
kehangatan bayi, perawatan tali pusat, mengganti popok setela
selesai BAB dan BAK dan memandikan bayi
E/Ibu mengerti dan bisa mengulangi penjelasan bidan
3) Menjelaskan tanda bahaya bayi baru lahir, seperti bayi tidak mau
menyusu, kejang- kejang, lemah, sesak nafas (lebih besar atau sama
dengan 60 kali/menit) tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam,
bayi merintih atau menangis terus-menerus, tali pusar kemerhaan
sampai dinding perut, berbau atau bernanah, demam/panas tinggi,
mata bayi bernanah, diare/buang air besar cair lebih dari 3 kali
sehari, kulit dan mata bayi kuning, tinja bayi saat buang air besar
berwarna pucat dan segera membawa ke fasilitas kesehatan jika
menemui 1 atau lebih tanda bahaya tersebut.
E/Ibu memahami penjelasan dari bidan
4) Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya dengan adekuat dan
memberikan ASI eksklusif pada bayinya selama 6 bulan.
E/Ibu selalu menyusui bayinya setiap bayi menangis atau setiap 2
jam sekali dan akan memberikan ASI eksklusif kepada bayinya
5) Memberitahu ibu untuk menjaga suhu tubuh bayi agar tidak
kedinginan.
E/Ibu paham dan mau membedong bayinya
6) Memberitahu ibu untuk mencuci tangan sebelum dan setelah
memegang bayi
E/Ibu bersedia melakukannya
7) Menyepakati kunjungan ulang tanggal 20 April 2020 atau sewaktu-
waktu bila ada keluhan atau terdapat tanda bahaya pada bayi
E/Ibu menyepakati
313
2. Kunjungan Neonatus II (6 Hari Post Partum)
Tanggal : 20 April 2020
Pukul : 08.20 WIB
Tempat : PMB Siti Rohmani, S.ST
a. Data Subyektif
Ibu mengatakan bayinya dalam keadaan sehat, bayi menangis kuat, bayi
tidur pulas dan menangis saat lapar, BAB, BAK dan saat dimandikan.
Bayi minum ASI tiap kali menangis, bayi tidak rewel. BAK 6-8 kali
sehari, lancar warna kuning jernih. BAB 2-3 kali sehari warna kuning,
konsistensi lunak. Tali pusat lepas pada hari ke-5.
b. Data Obyektif
1) Pemeriksaan Umum
1. Keadaan umum : Baik
2. Kesadaran : Composmentis
3. TTV : N : 124 x/menit S : 36,7°C
R : 42 x/menit
4. BB : 3100 gram
5. PB :51 cm
2) Pemeriksaan Fisik
Mata bersih, tidak ada secret, sclera putih, konjungtiva merah
muda, tidak ada pernafasan cuping hidung, bibir lembab, tidak ada
retraksi dada, pernafasan teratur, tali pusat sudah lepas, perut tidak
kembung, genetalia bersih, tidak ada kelainan diekstremitas, warna
kulit kemerahan.
c. Analisa
Bayi Ny.”T” neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan usia 6 hari
dengan keadaan normal.
d. Penatalaksanaan Jam : 08.30 WIB
1) Menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa bayi dalam keadaan
baik
E/Ibu terlihat lega dan merasa senang
314
2) Menganjurkan ibu untuk menyusui bayi maksimal setiap 2 jam
sekali atau sesering mungkin
E/Ibu bersedia mengikuti anjuran bidan
3) Mengingatkan ibu untuk selalu mencuci tangan sebelum dan setelah
memegang bayi.
E/Ibu mengerti dan bersedia
4) Mengingatkan ibu untuk imunisasi BCG dan Polio 1 pada bayinya
pada usia 0-1 bulan.
E/Ibu mengerti dan bersedia untuk imunisasi
5) Mendiskusikan kembali mengenai asuhan pada bayi meliputi
merawat bayi agar tetap hangat, tanda bahaya pada bayi, dan
perawatan sehari-hari, serta pemberian ASI eksklusif.
E/Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan
6) Menyepakati kunjungan ulang pada tanggal 12 Mei 2020 atau
sewaktu-waktu jika ada keluhan.
E/Ibu menyepakati
3. Kunjungan Neonatus III (28 Hari Post Partum)
Tanggal : 12 Mei 2020
Pukul : 10.30 WIB
Tempat : Rumah Ny.”T”
a. Data Subyektif
Ibu mengatakan bayinya dalam keadaan sehat, tidak ada keluhan, bayi
menangis kuat, bayi minum ASI tiap kali menangis, bayi tidur pulas
dan menangis saat lapar, BAB, BAK dan saat dimandikan, BAK 8-10
kali sehari, lancer, warna kuning jernih, BAB 1-2 kali sehari,
konsistensi lembek, warna kekuningan.
b. Data Obyektif
1) Pemeriksaan Umum
a) Keadaan umum : Baik
b) Kesadaran : Composmentis
315
c) TTV : N : 122x/menit S : 36,9°C
R : 40 x/menit
d) BB : 3900 gram
e) PB : 52cm
2) Pemeriksaan Fisik
Mata bersih, tidak ada secret, seclera putih, konjungtiva merah
muda, tidak ada pernafasan cuping hidung, bibir lembab, bibir
kemerahan, tidak ada oral trash, tidak ada retraksi dada, pernafasan
teratur, perut tidak kembung, pusar bersih, genetalia bersih, tidak ada
kelainan ekstermitas, warna kulit kemerahan.
c. Analisa
Bayi Ny.”T” neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan usia 28 hari
keadaan normal
d. Penatalaksanaan Jam : 10.40 WIB
1) Menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa bayi dalam keadaan
sehat
E/Ibu terlihat lega dengan keadaan bayinya
2) Mengingatkan ibu untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah
memegang bayi.
E/Ibu selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi
3) Mendiskusikan kembali mengenai perawatan bayi sehari-hari dan
tanda bahaya pada bayi
E/Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan akan
memantau keadaan bayinya.
4) Memberikan motivasi pada ibu agar tetap menyusui ASI selama 6
bulan tanpa makanan tambahan lainnya dan mengingatkan kembali
pada ibu untuk menyusui bayi maksimal setiap 2 jam sekali atau
sesering mungkin.
E/Ibu bersedia melanjutkan anjuran bidan
5) Mengingatkan ibu untuk menimbang bayinya ke posyandu setiap
bulan dan melakukan imunisasi sesuai jadwal.
316
E/Ibu mengerti dan bersedia ke posyandu setiap bulan
KARISMA HAYU ISLAMI
E. Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana
1. Kunjungan Keluarga Berencana I
Tanggal : 14 Mei 2020
Pukul : 14.10 WIB
Tempat : Rumah Ny.”T”
a. Data Subyektif
1) Setelah melahirkan sampai sekarang ibu belum melakukan hubungan
seksual.
2) Ibu mengatakan belum mengerti tentang macam-macam KB yang
dapat digunakan pascasalin dan ibu menyusui
3) Ibu tetap ingin memberikan ASInya secara ekslusif kepada bayinya
b. Data Obyektif
1) Pemeriksaan umum :
a) Keadaan umum : baik
b) Kesadaran : composmentis
c) TTV : TD : 110/80 mmHg N : 80x/menit
S : 36,5°C Rr : 20x/menit
d) BB : 62 kg
e) TB : 158 cm
2) Pemeriksaan fisik
a) Kepala
Inspeksi : Bersih, simetris, warna rambut hitam, tidak rontok,
persebaran rambut merata, tidak ada lesi
Palpasi : Tidak ada benjolan abnormal, tidak ada nyeri tekan
b) Muka
Inspeksi : Simetris, bersih, tidak sembab, tidak pucat
Palpasi : Tidak oedem
317
c) Mata
Inspeksi :Simetris, bersih, tidak ada sekret, konjungtiva
merah muda, sklera putih
Palpasi : Kelopak mata tidak oedema.
d) Hidung
Inspeksi : Simetris, tidak ada pernafasan cuping hidung, tidak
ada sekret dan polip
e) Mulut
Inspeksi : Simetris, bersih, bibir lembab, tidak ada stomatitis,
tidak ada perdarahan gusi, tidak ada karies, lidah
bersih
f) Telinga
Inspeksi : Simetris, bersih, tidak ada serumen
g) Leher
Inspeksi : Simetris, bersih, tidak ada pembesaran kelenjar
tyroid dan limfe tidak ada bendungan vena jugularis.
h) Dada
Inspeksi :Simetris, bersih, tidak ada retraksi dinding dada
Palpasi : tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan
Auskultasi : paru-paru: pernafasan teratur, tidak ada suara
wheezing dan ronchi, bunyi jantung normal dan
teratur.
Perkusi : Jantung pekak, paru-paru sonor
i) Payudara
Inspeksi :Simetris, bersih, kedua puting menonjol,
hiperpigmentasi areola
Palpasi : tidak ada benjolan abnormal, tidak ada nyeri tekan,
ada pengeluaran ASI
j) Axilla
Inspeksi : bersih
318
Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar limfe, tidak ada
nyeri tekan, tidak ada massa
k) Abdomen
Inspeksi :simetris, tidak ada bekas luka operasi, kandung
kemih kosong
Palpasi : tidak ada nyeri tekan, tidak ada massa
l) Genetalia
Inspeksi : Bersih, terdapat pengeluaran cairan berwarna putih
(lochea alba), terdapat luka bekas jahitan di
perineum, kondisi jahitan bersih dan kering, tidak
ada odema dan varises, tidak ada condiloma
akuminata dan condiloma matalata
Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar bartolini dan scene
m) Anus
Inspeksi : Tidak ada haemoroid
n) Ekstremitas
Inspeksi : Simetris, kuku bersih, tidak ada gangguan gerak,
jumlah jari tangan dan kaki lengkap, tidak polidaktil
dan tidak sindaktil
Palpasi : Tidak oedem dan tidak varises
c. Analisa
Ny.”T” P10001, usia 25 tahun, calon peserta KB pascasalin, keadaan
umum baik.
d. Penatalaksanaan Jam :14.20 WIB
1) Menjelaskan hasil pemeriksaan bahwa Ibu dalam keadaan sehat.
E/Ibu lega dirinya dalam keadaan sehat.
2) Menanyakan pada klien tujuan menggunakan KB.
E/Ibu ingin menjarakkan kehamilan dan masih belum ingin hamil
lagi
3) Menjelaskan macam-macam KB yang dapat dipakai ibu.
319
a) MAL : kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI
ekslusif selama 6 bulan.
Keuntungan : efektivitas sangat tinggi, tidak mengganggu
senggama, tidak perlu pengawasan medis
Kerugian : perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar
segera menyusui 30 menit setelah bayi Lahir
b) Kondom : selubung atau sarung karet yang terbuat dari
berbagai bahan lateks yang dipasang pada penis pada saat
berhubungan seksual. Cara kerjanya kondom menggalangi
sperma bertemu dengan sel telur.
Keuntungan : efektif jika digunakan dg benar, tidak mengaggu
produksi ASI, murah dan tersedia diberbagai tempat,
mencegah penyakit PMS
Kerugian : efektivitas tidak terlalu tinggi tergantung pada
pemakaian, dapat terjadi kebocoran, pengurangan sensitifitas
pada penis
c) IUD : alat berukuran kecil yang dimasukkan ke dalam rahim.
Keuntungan : efektivitas sangat tinggi, merupakan kontrasepsi
jangka panjang, tidak mempengaruhi kualitas ASI
Kerugian : perdarahan diantara haid, meningkatkan risiko
radang panggul, klien tidak bisa melepas sendiri, tidak
mencegah PMS
d) Implant : salah satu metode kontrasepsi jangka panjang yang
dapat Ibu pilih untuk menjarakkan kehamilan. KB Implan
dipasang bawah kulit Ibu dan hanya mengandung hormon
progesteron. Hormon tersebut dilepaskan dalam jumlah kecil
secara terus menerus ke dalam aliran darah
Keuntungan : Perlindungan jangka panjang hingga tiga tahun,
Implan dapat dilepas kapan saja, termasuk saat muncul efek
samping yang tidak diinginkan, Dapat kembali ke masa subur
dengan cepat setelah implan dilepas, tidak perlu repot
320
mengingat untuk konsumsi pil KB atau suntik KB secara
teratur.
Kerugian : Tidak dapat mencegah penyakit menular seksual,
Biaya lebih mahal, Implan harus dikeluarkan setelah tiga
tahun, Implan mudah berpindah dari posisi semula.
e) Suntik progestin (suntik kb 3 bulan) : kontrasepsi yang
diberikan dengan disuntikkan setiap 3 bulan.
Keuntungan : efektif, sederhana, tidak mengganggu proses
laktasi
Kerugian : dapat terjadi gangguan haid, penambahan berat
badan, bisa menimbulkan jerawat
E/Ibu mengerti dan paham macam-macam KB yang bisa dipakai
saat menyusui.
4) Mendiskusikan KB yang akan dipakai ibu.
E/Ibu ingin menggunakan KB suntik 3 bulan
5) Menganjurkan ibu untuk datang ke fasilitas kesehatan/PMB jika
ingin memasang KB atau jika sewaktu-waktu ada keluhan.
E/Ibu bersedia
2. Kunjungan Keluarga Berencana II
Tanggal : 3 Juni 2020
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : PMB Siti Rohmani, S.ST
a. Data Subyektif
1) Ibu belum melakukan hubungan seksual setelah persalinan.
2) Ibu belum menstruasi sejak melahirkan
3) Ibu ingin menggunakan KB hormonal (Suntik 3 Bulan).
4) Ibu belum mengerti sepenuhnya mengenai KB suntik 3 bulan.
5) Ibu masih menyusui secara ekslusif dan bayinya saat ini berusia 50
hari.
6) Ibu berencana akan menggunakan KB suntik 3 bulan saat ini.
321
b. Data Obyektif
1) Pemeriksaan umum
a) Keadaan umum : Baik
b) Kesadaran : Composmentis
c) TTV : TD : 100/70 mmHg
S : 36,6°C
N : 87x/menit
Rr : 22x/menit
d) BB : 60 kg
2) Pemeriksaan fisik
Muka tidak pucat, tidak sembab, konjungtiva merah muda, sklera
putih, tidak ada pembengkakan pada palpebra, tidak ada benjolan
pada payudara, tidak ada nyeri tekan pada payudara, puting bersih,
hyperpigmentasi areola dan papilla mammae, ASI lancar, TFU
tidak teraba, genetalia bersih, tidak hemoroid, pada ekstermitas
tidak oedem dan tidak varises.
c. Analisa
Ny.”T” P10001, usia 25 tahun, calon akseptor KB suntik 3 bulan, keadaan
umum baik.
d. Penatalaksanaan Jam : 09.15 WIB
1) Memberitahu hasil pemeriksaan bahwa ibu bisa menggunakan KB
suntik 3 bulan/tidak ada kontraindikasi.
E/Ibu terlihat senang
2) Memberikan kesempatan pada ibu untuk mengungkapkan KB yang
sudah dipilih sesuai dengan kebutuhannya dan persetujuan dari
suami.
E/Ibu merasa bahwa KB tersebut sesuai dengan kebutuhannya dan
mengatakan bahwa dirinya dan suami memilih KB suntik 3 bulan.
3) Menjelaskan pada ibu secara rinci tentang KB suntik 3 bulan :
KB suntik 3 bulan adalah merupakan metode kontrasepsi yang
diberikan secara intramuscular setiap tiga bulan.
322
Cara kerja : Setelah disuntikkan, hormon progestogen akan
dilepaskan secara bertahap ke dalam aliran darah. Hormon di
dalam KB suntik ini dapat mencegah proses pembuahan
dengan tiga cara, yaitu :
- Menghentikan ovulasi atau proses pelepasan sel telur dari
ovarium setiap bulannya
- Mengentalkan lendir di leher rahim, sehingga sperma
terhalang dan sulit masuk ke rahim untuk membuahi sel telur
- Membuat lapisan rahim menjadi lebih tipis, sehingga bila ada
sel telur yang berhasil dibuahi, sel tersebut tidak akan
berkembang karena kondisi rahim tidak mendukungnya
Keuntungan : efektifitas tinggi, sederhana pemakainnya,
injeksi hanya dilakukan 4 kali dalam setahun, cocok untuk ibu
menyusui, dapat mencegah kanker endometrium, kehamilan
ektopik serta beberapa penyakit akibat radang panggul.
Kerugian : gangguan haid, timbul jerawat, berat badan
meningkat, pusing, nyeri pada daerah suntikan
E/Ibu sudah mengerti dengan penjelasan mengenai alat
kontrasepsi suntik 3 bulan dan tetap akan menggunakan KB suntik
3 bulan.
4) Memberitahu ibu terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan KB
suntik 3 bulan, sebaiknya KB suntik 3 bulan dilakukan bila ibu
sudah mendapatkan haid pertama kali karena jika dilakukan ketika
ibu belum mendapatkan haid, ibu harus menggunakan alat
kontrasepsi lain ketika melakukan hubungan seksual selama 7 hari
agar KB suntik 3 bulan bisa benar-benar efektif.
E/Ibu tetap akan menggunakan KB suntik 3 bulan pada saat ini.
5) Melakukan informed consent sebelum melakukan suntikan.
E/Ibu setuju untuk disuntik.
6) Menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk penyuntikan
seperti spuit 3 cc, kapas alkohol dan Depo progestin.
323
E/Alat telah disiapkan.
7) Menyuntikkan KB suntik 3 bulan Depo Progestin 3 cc secara IM
Intramuskular (IM) di bokong 1/3 SIAS (Spina Iliaka Anterior
Superior).
E/Penyuntikan sudah dilakukan, tidak ada perdarahan..
8) Menyepakati kunjungan ulang 3 bulan yang akan datang pada
tanggal 26 Agustus 2020 atau sewaktu-waktu jika ada keluhan.
E/Ibu menyepakati
KARISMA HAYU ISLAMI
324
BAB IV
PEMBAHASAN
Pada bab ini penulis membahas kesesuaian antara tinjauan teori dalam bab
2 dengan tinjauan kasus dalam bab 3. Pembahasan ini bertujuan untuk
merumuskan kesenjangan-kesenjangan antara teori dengan kasus nyata pada
asuhan kebidanan secara continuity of care pada Ny.”T” G1P00000 selama masa
kehamilan trimester III, masa persalinan, masa nifas, neonatus, dan pemakaian
kontrasepsi yang dilakukan mulai tanggal 11 April 2020 di PMB Siti Rohmani,
S.ST Kabupaten Madiun dengan menggunakan standart asuhan kebidanan yang
didokumentasikan dengan SOAP. Berdasarkan kasus Ny.”T”, terdapat beberapa
kesenjangan dan kesamaan antara teori dan praktik, diantaranya sebagai berikut:
A. Kehamilan
Pada biodata didapatkan bahwa Ny.”T” berusia 25 tahun. Menurut
Walyani (2015) umur perlu diketahui guna mengetahui apakah klien dalam
kehamilan yang berisiko atau tidak, usia dibawah 16 tahun dan diatas 35
tahun merupakan umur yang berisiko tinggi untuk hamil. Jadi dapat
disimpulkan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus karena Ny
“T” masih dalam rentan usia 16 – 35 tahun.
Pada tinjauan kasus, ibu periksa hamil sebanyak 11 kali yaitu 2 kali pada
trimester I, 4 kali pada trimester II, dan 5 kali pada trimester III. Menurut
Kemenkes RI (2019), kunjungan ANC minimal harus dilakukan 4 kali yaitu
minimal 1 kali pada trimester pertama, minimal 1 kali pada trimester kedua,
dan minimal 2 kali pada trimester ketiga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
pada kasus ini tidak ada kesenjangan antara kasus dan teori.
Jumlah score KSPR Ny “T” adalah 2, menurut Rohjati dalam Wijaya
(2019), skor 2 merupakan Kehamilan Risiko Rendah (KRR), untuk ibu hamil
dengan kehamilan risiko rendah, persalinan dapat dilakukan secara normal
dan dapat ditolong oleh bidan. Hal ini menunjukkan tidak adanya
kesenjangan antara teori dan kasus.
325
Ny.”T” memiliki tinggi badan 158 cm. Menurut Walyani (2015), tinggi
badan kurang dari 145 cm ada kemunginan terjadi Cepalo Pelvic
Disproposian (CPD). Sehingga dilihat dari tinggi badan Ny.”T” tidak ada
kemungkinan terjadi CPD. Berat badan Ny “T” sebelum hamil adalah 58 kg,
berat badan sekarang adalah 67 kg, kenaikan berat badan selama hamil 9 kg,
hasil perhitungan IMT 23,2. Manurut Walyani (2015) IMT normal adalah
19,8 - 26. Pada IMT normal rekomendasi kenaikan berat badan selama hamil
adalah 11,5 – 16 kg. Dari hasil penimbangan berat badan dan penghitungan
IMT pada Ny ”T”, dapat disimpulkan hasil IMT normal tetapi kenaikan berat
badan tidak sesuai dengan rekomendasi yang ditetapkan, sehingga dapat
disimpulkan ada kesenjangan antara teori dan kasus dan telah dilakukan
penatalaksanaan berupa anjuran untuk menambah porsi makan.
Pada pemeriksaan auskultasi didapatkan hasil bahwa DJJ frekuensi
146 kali/menit, jelas dan kuat, punctum maksimum 3 jari kanan bawah pusat.
Menurut Walyani (2015) DJJ normal yaitu 120–160 x/menit, jika DJJ <120
atau >160 maka kemungkinan ada kelainan pada janin atau plasenta.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa DJJ janin Ny.”T” normal.
Ny.”T” G1P00000 umur kehamilan 39+1
, janin tunggal, hidup, presentasi
kepala, puka, intrauterin, keadaan umum ibu dan janin baik. Menurut Diana
(2017) diagnose kebidanan pada kehamilan adalah Ny. . . .(G) . . . .(P). . .
.(Ab). . . .(Ah) Usia kehamilan . . .tunggal atau ganda, hidup atau mati, letak
kepala atau bokong, intra uterin atau ekstrauterin, keadaan jalan lahir nornal
atau tidak, keadaan umum ibu dan janin baik atau tidak, sehingga dapat
disimpulkan tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus
Evaluasi didapatkan dari respon ibu terhadap penatalaksanaan yang
diberikan yaitu ibu mengatakan bersedia untuk menambah porsi makannya,
sehingga ibu memahami hasil pemeriksaan dan nasehat yang diberikan.
B. Persalinan
1. Kala I
Kala I pada kasus ini didasari dengan adanya kenceng-kenceng
yang dirasakan Ny.”T” mulai tanggal 15 April 2020 jam 08.00 WIB.
326
Pada saat pemeriksaan jam 12.00 WIB pembukaan 4 cm dengan
frekuensi his 3x dalam 10 menit lamanya 40 detik. Menurut Walyani dan
Purwoastuti (2015), frekuensi dan lama kontraksi uterus pada fase aktif
adalah 3 kali atau lebih dalam 10 menit dan berlangsung selama 40 detik
atau lebih. Sehingga dari teori dan kasus tidak ada kesenjangan. Pada jam
15.30 WIB dilakukan pemeriksaan dalam dan ditemukan pembukaan 10
cm. Pada kasus Ny.”T” kala I fase aktif berlangsung selama 3,5 jam
sedangkan, menurut Walyani dan Purwoastuti (2015) fase aktif
berlangsung selama 6 jam. Sehingga dapat disimpulkan terdapat
kesenjangan antara teori dan kasus tetapi tidak menganggu proses
persalinan ibu.
2. Kala II
Pada kasus Ny.”T” mengalami kontraksi yang semakin lama
semakin sering kemudian pembukaan lengkap dialami ibu pada tanggal
15 April 2020 pukul 15.30 WIB, pada kala pengeluaran janin his sangat
kuat, teratur terkoordinasi dan lama, vulva membuka dan perineum
meregang, dengan his dan mengejan yang terpimpin kepala lahir diikuti
seluruh badan janin (Walyani dan Purwoastuti, 2015).
Pada kala II lamanya berlangsung 30 menit yang dimulai dari
pembukaan lengkap pada jam 15.30 sampai lahirnya bayi pukul 16.00
WIB, sedangkan menurut Walyani dan Purwoastuti (2015) lama kala II
pada primipara berlangsung 1,5 - 2 jam. Sehingga dapat disimpulkan
terdapat kesenjangan antara teori dengan kasus tetapi proses persalinan
berlangsung dengan normal.
Pertolongan persalinan kala II dilaksanakan sesuai dengan 60
langkah APN secara runtut. Hal ini sesuai dengan teori JNPK-KR
(2017).
3. Kala III
Setelah bayi lahir kontraksi rahim berhenti sebentar, uterus teraba
keras beberapa saat kemudian timbul his pengeluaran dan pelepasan uri.
Plasenta lahir pukul 16.05 WIB, dengan jumlah estimasi perdarahan ±
327
200 cc. Total waktu yang dibutuhkan untuk pelepasan dan pengeluaran
plasenta adalah 5 menit. Menurut Walyani dan Purwoastuti (2015),
seluruh proses kala III biasanya berlangsung 5-30 menit setelah bayi
lahir. Menurut Suprijati (2014), pada persalinan pervaginam kehilangan
darah sekitar (200-500 cc). Sehingga dapat disimpulkan tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
4. Kala IV
Tahapan ini digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap
bahaya komplikasi perdarahan pascapersalinan, pemantauan kala IV
dilakukan setiap 15 menit sekali dalam 1 jam pertama setelah melahirkan
selanjutnya setiap 30 menit pada satu jam berikutnya, pengawasan kala
IV berisi data tentang tekanan darah, nadi, temperatur, TFU, kontraksi,
kandung kemih dan perdarahan, pantau temperatur tubuh setiap jam
dalam 2 jam pertama pasca persalinan dan memastikan kandung kemih
kosong (JNPK-KR, 2017). Dalam kasus Ny.”T” kala IV pengawasan
dimulai setelah proses heacting selesai dan ibu sudah merasa nyaman
yaitu pukul 16.30-18.15 WIB. Sedangkan menurut Yulizawati, dkk
(2019), kala IV adalah kala dimana 1-2 jam setelah lahirnya plasenta. Ini
menunjukkan terdapat kesenjangan antara teori dengan pelaksanaannya
tetapi dari hasil observasi menunjukkan ibu dalam keadaan normal.
C. Nifas
Pada saat hari pertama postpartum perhatian ibu terfokus pada dirinya
sendiri dan masih tergantung dengan orang sekitarnya serta belum bisa
bertanggungjawab dalam mengurus bayinya, hal tersebut sesuai dengan teori
yang menyebutkan ibu berada pada fase taking in. Menurut Nugroho,dkk
(2014), fase taking in merupakan periode ketergantungan, yang berlangsung
dari hari pertama sampai hari ke dua setelah melahirkan. Ibu terfokus pada
dirinya sendiri, sehingga cenderung pasif terhadap lingkungannya.
Ketidaknyamanan yang dialami antara lain rasa mules, nyeri pada luka
jahitan, kurang tidur dan kelelahan. Hal yang perlu diperhatikan pada fase ibi
adalah istirahat cukup, komunikasi yang baik dan asupan nutrisi.
328
Pada pemeriksaan nifas I (6 jam postpartum) didapatkan hasil ASI belum
lancar, bayi sering menyusu, TFU 2 jari bawah pusat dan lokhea rubra warna
merah kehitaman. Menurut Suprijati (2014) TFU setelah plasenta lahir adalah
2 jari bawah pusat. Serta menurut Nugroho, dkk (2014) lokhea pada hari 1-3
adalah lokhea rubra berwarna merah kehitaman.
Pada kunjungan nifas ke II (hari ke 6 postpartum), didapatkan hasil
pemeriksaan payudara bersih, tidak ada nyeri tekan, TFU pertengahan pusat
simpisis, luka jahitan perineum baik dan tidak ada tanda infeksi, ASI lancar,
lokhea sanguinolenta berwarna putih bercampur merah. Menurut Suprijati
(2014) TFU pada 1 minggu postpartum adalah di pertengahan pusat simpisis
dan menurut Nugroho,dkk (2014) lokhea pada hari 3-7 postpartum adalah
lokhea sanguinolenta berwarna putih bercampur merah.
Pada kunjungan nifas ke III (hari ke 30 postpartum), didapatkan hasil
ASI keluar lancar, TFU tidak teraba, lochea alba warna putih. Menurut
Suprijati (2014) TFU pada 4-6 minggu postpartum tidak teraba, serta menurut
Nugroho,dkk (2014) lokhea yang keluar pada saat lebih dari 14 hari
postpartum adalah lokhea alba berwarna putih. Sehingga berdasar hal diatas
dapat disimpulkan masa nifas Ny.”T” berjalan normal dan fisiologis.
Selama kunjungan ibu tidak ada keluhan dan proses nifas berjalan
dengan normal sesuai teori. Kondisi psikologis ibu tidak ada masalah.
Penyuluhan yang telah diberikan dilaksanakan ibu dengan sebaik mungkin.
Ini menunjukkan kesesuaian antara pelaksanaan pada teori dan kasus.
D. Neonatus
Dalam 6 jam pertama, bayi ny.”T” sudah bisa BAK 3 kali, warna kuning
jernih, BAB 1 kali konsistensi lunak, warna kehitaman. Menurut Tando
(2016) dalam waktu 24 jam, bayi mengeluarkan mekonium dan berkemih 20-
30 cc urine per hari kemudian meningkat menjadi 100-200 cc/hari. Kotoran
yang dikeluarkan bayi pada hari-hari pertama disebut mekonium. Mekonium
adalah ekskresi gastrointestinal bayi yang diakumulasi dalam usus sejak masa
janin, yaitu pada usia kehamilan 16 minggu.
329
Bayi Ny.”T” diberi minum ASI setiap 2 jam, menurut Tando (2016) ASI
merupakan makanan yang terbaik bagi bayi dan mengandung zat gizi yang
sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, baik kualitas maupun
kuantitas. ASI diberikan sesuai kebutuhan bayi, biasanya bayi merasa lapar
setelah 2-4 jam. Jagan beri susu formula sebelum usia bayi 6 bulan.
Tali pusat bayi dibungkus dengan menggunakan kasa steril dan kering
tanpa dibubuhi ramuan atau alkohol, segera dibersihkan jika terkena kotoran,
kasa diganti setiap mandi atau saat kotor. Menurut Tando (2016) sisa tali
pusat sebaiknya dipertahankan dalam keadaan terbuka, ditutupi kasa
bersih/steril, jika tali pusat terkena urine/feses, harus segera dicuci dengan
menggunakan air bersih dan sabun kemudian dikeringkan.
Pada kunjungan I keadaan umum bayi baik, pemeriksaan tanda-tanda
vital bayi didapatkan hasil suhu 36,8°C, nadi 130x/menit, respirasi 48x/menit.
Pada kunjungan ke II didapatkan hasil suhu 36,7°C, nadi 124x/menit,
respirasi 42x/menit dan pada kunjungan ke III didapatkan hasil suhu 36,9°C,
nadi 122x/menit, respirasi 40x/menit. Menurut Tando (2016) suhu bayi
normal adalah 36,5-37,5°C , pernafasan bayi normal adalah 30-60x/menit,
nadi dihitung dengan waktu satu menit normalnya 120-140x/menit. Sehingga
tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Pemberian vitamin K1 diberikan 1 jam setelah bayi lahir dan imunisasi
Hb 0 diberikan pada saat 2 jam setelah lahir. Menurut JNPK-KR (2017)
untuk vitamin K1 1 mg diberikan 1 jam kelahiran dan Hb 0 diberikan 1 jam
setelah pemberian vitamin K1 dan menurut Tando (2016) pemberian Hb 0
pada usia 0-7 hari. Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dengan kasus.
Bayi Ny.”T”, usia bayi baru lahir normal, cukup bulan, sesuai masa
kehamilan, keadaan umum baik. Menurut Diana (2017)
By.Ny....usia...dengan bayi baru lahir, keadaan umum baik. Tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus. Semua poin dari intervensi dilaksanakan
sebagai implementasi pada bayi, untuk implementasi selanjutnya dilakukan
sesuai keluhan pasien. Ibu melaksanakan anjuran yang diberikan. Keadaan
bayi sehat. Ini menunjukkan terdapat kesesuaian antara teori dan kasus nyata.
330
Bidan melakukan evaluasi secara sistematis dan berkesinambungan untuk
melihat keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan, sesuai dengan
perubahan perkembangan kondisi klien. Hasil evaluasi segera dicatat dan
dikomunikasikan pada klien dan/atau keluarga. Hasil evaluasi harus segera
ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi klien/pasien.
E. Keluarga Berencana (KB)
Pada ANC, penulis tidak memberikan konseling KB Pascasalin.
Kunjungan KB ke I atau konseling KB dilakukan pada saat kunjungan nifas
ke III (30 hari postpartum). Sedangkan menurut Kemenkes RI (2014) pada
standar ANC 10T, ibu hamil diberikan pengarahan tentang pentingnya ikut
KB setelah persalinan untuk menjarangkan kehamilan dan agar ibu punya
waktu merawat kesehatan diri sendiri, anak, dan keluarga. Jadi dapat
disimpulkan terdapat kesenjangan antara teori dan kasus.
Kunjungan KB ke II atau saat pemasangan KB dilakukan pada 50 hari
postpartum. Sedangkan menurut Mulyani dan Rinawati (2013), kontrasepsi
pasca persalinan merupakan inisiasi pemakaian metode kontrasepsi dalam
waktu 6 minggu pertama pasca persalinan untuk mencegah terjadinya
kehamilan yang tidak diinginkan, khusunya pada 1-2 tahun pertama pasca
persalinan. Jadi dapat disimpulkan terdapat kesenjangan antara teori dan
kasus, yang seharusnya KB pascasalin dilakukan dalam waktu 6 minggu
pertama pascapersalinan (42 hari pasca persalinan) tetapi pada kasus
pemasangan KB dilakukan pada 50 hari pasca persalinan.
Pada saat kunjungan KB ke I, Ny.”T” mengatakan ingin menggunakan
KB yang tidak mengganggu produksi ASI dan Ny.”T” belum mengetahui
macam alat kontrasepsi yang bisa digunakannya. Penatalaksanaan yang
dilakukan adalah menjelaskan macam-macam alat kontrasepsi pascasalin,
cara kerja, keuntungan dan kerugiannya.
Pada saat akhir konseling Ny.”T” memutuskan untuk menggunakan alat
kontrasepsi suntik 3 bulan. Menurut Mulyani dan Rinawati (2013)
Kontrasepsi suntik 3 bulan merupakan kontrasepsi yang memiliki efektifitas
sangat tinggi dalam mencegah kekontrasepsi pascasalin hamilan dan memiliki
331
keuntungan yang relatif banyak seperti sederhana pemakaiannya, cocok untuk
ibu menyusui, dapat mencegah kanker endometrium, kehamilan ektopik, serta
beberapa penyakit radang pangggul.
Pada saat kunjungan KB ke I (30 hari postpartum) Ny.”T” belum
mengalami menstruasi dan belum melakukan hubungan seksual setelah
melahirkan. Menurut Manuaba (2013), sebagian besar menstruasi kembali
setelah 4 sampai 6 bulan.
Pada kunjungan KB ke II (50 hari postpartum) Ny.“T” ingin
menggunakan KB suntik 3 bulan, dari hasil pemeriksaan Ny.“T” tidak
memiliki kontraindikasi penggunaan KB suntik 3 bulan. Menurut Mulyani
dan Rinawati (2013) kontraindikasi KB suntik 3 bulan adalah ibu hamil atau
dicurigai hamil, ibu menderita kanker payudara atau riwayat kanker payudara,
ibu menderita diabetes mellitus yang disertai komplikasi, serta perdarahan
pervaginam yang belum jelas penyebabnya.
Ny.”T’ P10001 usia 25 tahun calon peserta KB pascasalin, keadaan
umum baik. Menurut Diana (2017) diagnose kebidnaan bagi calon peserta
KB adalah Ny...P...Ab...Ah...umur...tahun dengan calon akseptor KB... . Ini
menunjukkan tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Bidan melakukan rencana asuhan kebidanan secara komprehensif,
efektif, efisien, dan berdasarkan evidence based kepada klien/pasien dalam
bentuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dilaksanakan
secara mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Bidan melakukan evaluasi secara
sistematis dan berkesinambungan untuk melihat keefektifan dari asuhan yang
sudah diberikan, sesuai dengan perubahan perkembangan kondisi klien.
Evaluasi dilakukan segera setelah selesai melaksanakan asuhan sesuai kondisi
klien. Hasil evaluasi segera dicatat dan dikomunikasikan pada klien dan/atau
keluarga. Hasil evaluasi harus ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi
klien/pasien.
332
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pelaksanaan asuhan kebidanan yang diberikan secara
continuity of care pada Ny.”T” dimulai dari masa kehamilan trimester III,
persalinan, nifas, neonatus dan KB pascasalin di PMB Ny. Siti Rohmani,
S.ST, Dagangan Kabupaten Madiun dengan menggunakan pendekatan
manajemen kebidanan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Ny. ”T” G1P00000, usia 25 tahun dengan kehamilan fisiologis, asuhan
kebidanan dimulai pada usia kehamilan 39-40 minggu tanggal 11 April
2020. Selama masa kehamilan melakukan kunjungan ANC sebanyak 11
kali, selama kehamilan tidak ada keluhan khusus yang mengganggu.
Tetapi terdapat kesenjangan pada penambahan berat badan sesuai dengan
IMT.
2. Pada proses persalinan Ny.”T” keadaan ibu dan janin pada kala I
persalinan baik, kemajuan persalinan berlangsung normal. Setelah
pembukaan lengkap, dilakukan pertolongan persalinan. Setelah bayi lahir,
plasenta lahir lengkap. Pemantauan 2 jam postpartum setiap 15 menit pada
1 jam pertama dan setiap 30 menit pada 1 jam kedua. Perencanaan sesuai
dengan 60 langkah Asuhan Persalinan Normal. Penatalaksanaan sesuai
dengan perencanaan yang disusun. Hasil evaluasi menunjukkan persalinan
berlangsung normal, bayi lahir selamat dan sehat, tidak menunjukkan
adanya kelainan, keadaan ibu baik, plasenta lahir spontan dan lengkap,
terdapat laserasi derajat 2, kontraksi uterus keras, tidak ada perdarahan
abnormal.
3. Hasil pengkajian setiap kunjungan nifas pada Ny.”T” tidak ada keluhan
yang mengganggu, tidak ada masalah pada payudara dan produksi ASI,
proses involusi uteri sesuai dengan teori, luka perineum sudah mengering
saat kunjungan nifas ke III, perubahan warna lokhea normal, dan tidak
ditemukan tanda-tanda infeksi. Perencanaan sesuai dengan teori asuhan
333
pada ibu nifas. Penatalaksanaan dilakukan sesuai dengan perencanaan.
Setelah dilakukan evaluasi didapatkan hasil nifas berlangsung normal,
laktasi lancar, involusi dan lokhea normal, ibu menyusui secara eksklusif.
4. Bayi Ny.”T” dari hasil pengkajian tidak ada keluhan yang mengganggu
sampai kunjungan yang terakhir. Penambahan berat badan bayi sesuai,
TTV selalu normal, tidak ada tanda infeksi pada tali pusat dan tali pusat
dan tali pusat lepas saat bayi berusia 5 hari, bayi menyusu kuat, reflek
baik, tidak ada kelainan pada bayi, mendapat vitamin K1 pada 1 jam
setelah lahir dan imunisasi HB 0 pada 2 jam setelah lahir. Perencanaan
sesuai dengan teori asuhan kebidanan bayi baru lahir. Penatalaksanaan
sesuai dengan perencanaan. Hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan dasar
bayi terpenuhi, keadaan bayi sehat.
5. Saat kunjungan nifas ke III Ny.”T” menginginkan alat kontrasepsi yang
tidak mengganggu produksi ASI. Setelah dilakukan pemeriksaan,
didapatkan keadaan ibu sehat, tidak ada kelainan. Dari hasil pengkajian
disusun perencanaan termasuk KIE tentang alat kontrasepsi yang dapat
digunakan. Penatalaksanaan dilakukan sesuai dengan perencanaan. Hasil
evaluasi menunjukkan Ny.”T” memutuskan menggunakan KB suntik 3
bulan dan memahami cara kerja, keuntungan dan kelemahan KB suntik 3
bulan.
B. Saran
1. Bagi pasien dan keluarga
Diharapkan pasien dan keluarga mampu memelihara kesehatan, dan
memanfaatkan fasilitas pelayanan kebidanan yang ada. Serta pada
kehamilan selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara
rutin, melakukan persalinan dengan tenaga kesehatan terlatih, mampu
melakukan perawatan pada masa nifas dan neonatus serta melakukan KB
pascasalin dan segera datang ke fasilitas kesehatan bila ada tanda bahaya
baik pada ibu maupun bayi sehingga apabila ditemukan adanya penyulit
dapat segera memperoleh pelayanan yang optimal dan dapat meningkatkan
derajat kesehatan ibu dan bayi.
334
2. Bagi Profesi Bidan
Diharapkan petugas pelayanan kesehatan terutama bidan mampu
mendeteksi secara dini masalah-masalah ibu pada masa kehamilan,
persalinan, nifas, neonatus, dan KB pascsalin agar mendapatkan asuhan
yang sesuai sehingga bisa bersalin secara normal, masa nifas tanpa
komplikasi, perawatan neonatus dan pemilihan KB pascasalin dengan
tepat.
3. Bagi STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun
Diharapkan Institusi hendaknya selalu memberikan pengetahuan,
keterampilan dan meningkatkan pembelajaran materi yang terkini
mengenai asuhan kebidanan secara continuity of care kepada mahasiswa
kebidanan yang akan menjadi bidan yang bekerja dilapangan.
4. Bagi penulis selanjutnya
Diharapkan penulis dapat meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan dalam melaukan asuhan kebidanan secara continuity of care
sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan apa yang terjadi
dilapangan.
335
DAFTAR PUSTAKA
Affandi, B. 2014. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi. Jakarta: Bina
Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
Astuti, S., dkk. 2017. Asuhan Ibu Dalam Masa Kehamilan. Jakarta: Penerbit
Erlangga.
Badan Pusat Statistik (BPS). 2012.
https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/79. (diakses 6 Maret
2020).
Chuningham. 2013. Obstetri Williams. Jakarta: EGC.
Diana, S. 2017. Model Asuhan Kebidanan Continuity Of Care . Surakarta: Kekata
Publisher
Dinas Kesehatan Jawa Timur. 2019. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2018.
Jawa Timur: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. 2018. Profil Kesehatan Kabupaten Madiun
Tahun 2017. Kabupaten Madiun: Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
Handayani, S. 2010. Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana. Yogyakarta:
Pustaka Rihama.
Hartanto, H. 2009. Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi. Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan.
Hastuti, P., dkk. 2018. Kartu Skor Poedji Rochjati Untuk Skrining Antenatal.
Jurnal Link. Nomor 14 (2), : 111-113.
Jaringan Nasional Pelatihan Klinik – Kesehatan Reproduksi. 2017. Asuhan
Persalinan Normal. Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia.
Kementerian Kesehatan RI. 2010. Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu.
Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
__________. 2014. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97
Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa
Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan
Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Jakarta:
Kementerian Kesehatan RI.
__________. 2016. Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta: Kementerian
Kesehatan RI.
__________. 2018a. LAKIP DIREKTORAT KESEHATAN KELUARGA TAHUN
2017. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
336
__________. 2018b. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2017. Jakarta:
Kementerian Kesehatan RI.
__________. 2019a. Panduan Pelayanan Pasca Persalinan Bagi Ibu Dan Bayi
Baru Lahir. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI
__________. 2019b. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018. Jakarta:
Kementerian Kesehatan RI.
Kurniarum, A. 2016. Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Jakarta:
Kemen5terian Kesehatan RI.
Legawati. 2018. Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Malang : Wineka
Media
Manuaba, I.A.C., I.B.G.F. Manuaba dan I.B.G. Manuaba. 2010. Ilmu Kebidanan
Penyakit Kandungan dan KB untuk Pendidikan Bidan. Jakarta: EGC.
__________. 2013. Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB untuk
Pendidikan Bidan. Edisi 2. Jakarta: EGC.
Margareth, ZH. 2013. Asuhan Kehamilan, Persalinan dan Nifas. Yogyakarta:
Nuha Medika
Marmi. 2014. Asuhan Kebidanan Pada Masa Antenatal. Edisi Kedua.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Marmi dan K. Rahardjo. 2015. Asuhan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak
Prasekolah. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mulyani, N.S. 2013. ASI dan Pedoman Ibu Menyusui. Yogyakarta: Nuha Medika.
Mulyani, N.S., dan M. Rinawati. 2013. Keluarga Berencana dan Alat
Kontrasepsi. Yogyakarta: Nuha Medika.
Nugroho, T., dkk. 2014. Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas (Askeb 3).
Yogyakarta: Nuha Medika.
Prawiroharjdo, S. 2014. Ilmu Kebidanan. Edisi Keempat. Jakarta: Bina Pustaka
Sarwono Prawirohardjo.
Romauli, S. 2011. Buku Ajar Kebidanan 1 Konsep Asuhan Kehamilan.
Yogyakarta: Nuha Medika.
Saifuddin, A.B. 2010. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi. Jakarta:
Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
__________. 2013. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal
Neonatal. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
337
Sondakh, J.J.S. 2013. Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir.
Malang: Penerbit Erlangga.
Subekti, N.B. 2013. Buku Saku Kontrasepsi & Kesehatan Seksual Reproduktif.
Jakarta: EGC.
Sukarni, I., dan Margareth. 2013. Kehamilan, Persalinan, Dan Nifas. Yogyakarta:
Nuha Medika.
Sulistyawati, A. 2013. Pelayanan Keluarga Berencana. Jakarta: Salemba Medika.
Suprijati. 2014. Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas. Ponorogo: HMP Press.
Sutanto, A.V. 2018. Asuhan Kebidanan Nifas Dan Menyusui Teori Dalam Praktik
Kebidanan Profesional. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Tando, N.M. 2016. Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi dan Anak Balita. Jakarta:
EGC.
Tyastuti, S., dan H.P. Wahyuningsih. 2016a. Asuhan Kebidanan Kehamilan.
Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
__________. 2016b. Praktikum Asuhan Kebidanan Kehamilan. Jakarta:
Kementerian Kesehatan RI.
Walyani, E.S. 2015a. Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan. Yogyakarta: Pustaka
Baru Press.
__________. 2015b. Asuhan Kebidanan Masa Nifas & Menyusui. Yogyakarta:
Pustaka Baru Press.
Walyani, ES dan E. Purwoastuti. 2015. Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi
Baru Lahir. Yogyakarta: Pustaka Baru.
Wijaya, J. K. Inka. 2019. Gambaran Faktor Risiko Kegawatdaruratan Ginekologi
Di Rsud Dr. Habdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2018. Skripsi,
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Bandar Lampung.
World Health Organization (WHO). 2019. Maternal Mortality.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality dan
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/newborns-reducing-
mortality (diakses 6 Maret 2020).
Yulizawati, dkk. 2019. Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Persalinan. Sidoarjo:
Indomedia Pustaka.
367
Lampiran 26 : : Referensi data AKI dan AKB menurut WHO
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/newborns-reducing-mortality
368
SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP)
TANDA BAHAYA KEHAMILAN
Topik : Asuhan Ibu Hamil
Sub Topik : Tanda Bahaya Kehamilan dan Masalah dalam Kehamilan
Tanggal : 11 April 2020
Tempat : PMB Siti Rohmani, S.ST
Sasaran : Ny.”T”
A. Tujuan
Setelah mendapatkan penyuluhan ini, diharapkan ibu dapat mengetahui tentang
tanda bahaya kehamilan dan masalah lain dalam kehamilan
B. Media : Buku KIA
C. Metode : Ceramah dan Tanya Jawab
D. Langkah-langkah penyuluhan :
No Tahap Waktu Kegiatan
1. Pembukaan 1 menit Mengucapkan salam
Memperkenalkan diri
2. Pelaksanaan dan
penyampaian
materi
3 menit Menjelaskan tentang tanda bahaya
kehamilan dan masalah lain dalam
kehamilan
3. Diskusi 5 menit Menjawab pertanyaan dari ibu
4. Penutup 1 menit Penyimpulkan hasil penyuluhan
Memberi saran
Mengucapkan saran penutup
E. Materi
Tanda Bahaya Kehamilan :
1. Muntah terus dan tidak makan
2. Demam tinggi
3. Bengkak kaki, tangan, wajah, atau sakit kepala disertai kejang
4. Janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya
369
5. Perdarahan
6. Ketuban pecah sebelum waktunya
Masalah pada masa kehamilan :
1. Demam, menggigil dan berkeringat. Bila ibu berada di daerah endemis
malaria, menunjukkan adanya gejala penyakit malaria.
2. Terasa sakit pada saat kencing atau keluar keputihan atau gatal-gatal di
daerah kemaluan.
3. Batuk lama (lebih dari 2 minggu)
4. Jantung berdebar-debar atau nyeri di dada
5. Diare berulang
6. Sulit tidur dan cemas berlebihan
F. Daftar Pustaka
Kemenkes RI. 2016. Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta: Kementerian
Kesehatan RI.
372
SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP)
PERSIAPAN MELAHIRKAN
Topik : Asuhan Ibu Hamil
Sub Topik : Persiapan Melahirkan
Tanggal : 11 April 2020
Tempat : PMB Siti Rohmani, S.ST
Sasaran : Ny.”T”
A. Tujuan
Setelah mendapatkan penyuluhan ini, diharapkan ibu dapat mengetahui tentang
persiapan untuk melahirkan
B. Media : Buku KIA
C. Metode : Ceramah dan Tanya Jawab
D. Langkah-langkah penyuluhan :
No Tahap Waktu Kegiatan
1. Pembukaan 1 menit Mengucapkan salam
Memperkenalkan diri
2. Pelaksanaan dan
penyampaian
materi
3 menit Menjelaskan tentang persiapan
melahirkan
3. Diskusi 5 menit Menjawab pertanyaan dari ibu
4. Penutup 1 menit Penyimpulkan hasil penyuluhan
Memberi saran
Mengucapkan saran penutup
E. Materi
a. Menanyakan kepada bidan dan dokter tanggal perkiraan persalinan
b. Suami atau keluarga mendampingi ibu saat periksa kehamilan
c. Menyiapkan lebih dari 1 orang yang memiliki golongan darah yang sama
dan bersedia menjadi pendonor jika diperlukan
373
d. Mempersiapkan tabungan atau dana untuk biaya persalinan dan biaya
lainnya
e. Suami, keluarga dan masyarakat menyiapkan kendaraan jika sewaktu-
waktu diperlukan
f. Merencanakan melahirkan ditolong oleh dokter atau bidan di fasilitas
kesehatan
g. Memastikan ibu hamil dan keluarga menyepakati amanat persalinan dalam
stiker P4K dan sudah ditempelkan di depan rumah ibu hamil
h. Menyiapkan KTP, Kartu Keluarga, Kartu Jaminan Kesehatan Nasional
dan keperluan lain untuk ibu dan bayi yang akan dilahirkan
i. Mendaftarkan diri ke kantor BPJS Kesehatan setempat, atau tanyakan ke
petugas Puskesmas untuk mendapat kartu JKN
j. Merencanakan ikut Keluarga Berencana (KB) setelah bersalin.
Menanyakan kepada petugas kesehatan tentang cara ber-KB
F. Daftar Pustaka
Kemenkes RI. 2016. Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta: Kementerian
Kesehatan RI.
375
SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP)
TANDA-TANDA PERSALINAN
Topik : Asuhan Ibu Hamil
Sub Topik : Tanda-Tanda Persalinan
Tanggal : 11 April 2020
Tempat : PMB Siti Rohmani, S.ST
Sasaran : Ny.”T”
A. Tujuan
Setelah mendapatkan penyuluhan ini, diharapkan ibu dapat mengetahui tentang
tanda-tanda persalinan
B. Media : Buku KIA
C. Metode : Ceramah dan Tanya Jawab
D. Langkah-langkah penyuluhan :
No Tahap Waktu Kegiatan
1. Pembukaan 1 menit Mengucapkan salam
Memperkenalkan diri
2. Pelaksanaan dan
penyampaian
materi
3 menit Menjelaskan tanda-tanda
persalinan
3. Diskusi 5 menit Menjawab pertanyaan dari ibu
4. Penutup 1 menit Penyimpulkan hasil penyuluhan
Memberi saran
Mengucapkan saran penutup
E. Materi
Tanda-tanda persalinan :
1. Perut mulas-mulas yang teratur, timbulnya semakin sering dan semakin
lama
2. Keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir atau keluar cairan ketuban
dari jalan lahir
376
F. Daftar Pustaka
Kemenkes RI. 2016. Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta: Kementerian
Kesehatan RI.
378
SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP)
TANDA BAHAYA PERSALINAN
Topik : Asuhan Ibu Hamil
Sub Topik : Tanda Bahaya Persalinan
Tanggal : 11 April 2020
Tempat : PMB Siti Rohmani, S.ST
Sasaran : Ny.”T”
A. Tujuan
Setelah mendapatkan penyuluhan ini, diharapkan ibu dapat mengetahui tentang
tanda bahaya persalinan
B. Media : Buku KIA
C. Metode : Ceramah dan Tanya Jawab
D. Langkah-langkah penyuluhan :
No Tahap Waktu Kegiatan
1. Pembukaan 1 menit Mengucapkan salam
Memperkenalkan diri
2. Pelaksanaan dan
penyampaian
materi
3 menit Menjelaskan tanda bahaya
persalinan
3. Diskusi 5 menit Menjawab pertanyaan dari ibu
4. Penutup 1 menit Penyimpulkan hasil penyuluhan
Memberi saran
Mengucapkan saran penutup
E. Materi
1. Perdarahan lewat jalan lahir
2. Tali pusar atau tangan bayi keluar dari jalan lahir
3. Ibu mengalami kejang
4. Ibu tidak kuat mengejan
5. Air ketuban keruh dan berbau
6. Ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat
379
F. Daftar Pustaka
Kemenkes RI. 2016. Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta: Kementerian
Kesehatan RI.
381
SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP)
KEBUTUHAN DASAR IBU NIFAS
Topik : Asuhan Ibu Nifas
Sub Topik : Kebutuhan Dasar Ibu Nifas
Tanggal : 15 April 2020
Tempat : PMB Siti Rohmani, S.ST
Sasaran : Ny.”T”
A. Tujuan
Setelah mendapatkan penyuluhan ini, diharapkan ibu dapat mengetahui tentang
kebutuhan pada masa nifas
B. Media : Leaflet
C. Metode : Ceramah dan Tanya Jawab
D. Langkah-langkah penyuluhan :
No Tahap Waktu Kegiatan
1. Pembukaan 1 menit Mengucapkan salam
Memperkenalkan diri
2. Pelaksanaan dan
penyampaian
materi
10 menit Menjelaskan tanda bahaya pada
masa nifas
3. Diskusi 3 menit Menjawab pertanyaan dari ibu
4. Penutup 1 menit Penyimpulkan hasil penyuluhan
Memberi saran
Mengucapkan saran penutup
E. Materi
Masa nifas adalah masa dimulai beberapa jam sesudah lahirnya plasenta
sampai 6 minggu setelah melahirkan (Nugroho dkk, 2014). Masa nifas
dimulai setelah kelahira plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan
kembali seperti keadaan sebelum hamil yang berlangsung kira-kira 6 minggu
(Nugroho dkk, 2014).
Kebutuhan Dasar Masa Nifas :
382
1. Nutrisi dan cairan
lbu nifas memerlukan nutrisi dan cairan untuk pemulihan kondisi
kesehatan setelah melahirkan, cadangan tenaga serta untuk memenuhi
produksi air susu. Ibu nifas dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan akan
gizi sebagai berikut:
a) Mengkonsumsi makanan tambahan. kurang lebih 500 kalori tiap hari
b) Makan dengan diet gizi seimbang untuk memenuhi kebutuhan
karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral
c) Minum sedikitnya 3 liter setiap hari
d) Mengkonsumsi tablet besi selama 40 hari post partum
e) Mengkonsumsi vitamin A 200.000 IU
Zat-zat yang dibutuhkan ibu pasca persalinan antara lain :
a. Kalori
Kebutuhan kalori pada masa menyusui sekitar 400-500 kalori.
Wanita dewasa memerlukan 1800 kalori per hari. Sebaiknya ibu
nifas jangan mengurangi kebutuhan kalori, karena akan mengganggu
proses metabolisme tubuh dan menyebabkan ASI rusak.
b. Protein
Kebutuhan protein yang dibutuhkan adalah 3 porsi per hari. Satu
protein setara dengan tiga gelas susu, dua butir telur, lima putih telur,
120 gram keju, 1 ¾ gelas yoghurt, 120-140 gram
ikan/daging/unggas, 200-240 gram 1 tahu atau 5-6 sendok selai
kacang
c. Kalsium dan vitamin D
Kalsium dan vitamin D berguna untuk pembentukan tulang dan gigi.
Kebutuhan kalsium dan vitamin D didapat dari minum susu rendah
kalori atau berjemur di pagi hari. Konsumsi kalsium pada masa
menyusui meningkat menjadi 5 porsi per hari. Satu setara dengan 50-
60 gr keju, satu cangkir susu krim, 160 gr ikan salmon, 120 gr ikan
sarden, atau 280 gr tahu kalsium.
383
d. Magnesium
Magnesium dibutuhkan sel tubuh untuk membantu gerak otot. fungsi
syaraf dan memperkuat tulang. Kebutuhan magnesium didapat pada
gandum dan kacang-kacangan.
e. Sayuran hijau dan buah
Kebutuhan yang diperlukan sedikitnya tiga porsi sehari. Satu porsi
setara dengan ⅛ semangka, ¼ mangga, ¾ cangkir brokoli, ½ wortel,
¼ - ½ cangkir sayuran hijau yang telah dimasak, satu tomat.
f. Karbohidrat kompleks
Selama menyusui, kebutuhan karbohidrat kompleks diperlukan 6
porsi per hari. Satu porsi setara dengan ½ cangkir nasi, ¼ cangkir
jagung pipil, 1 porsi sereal atau oat, 1 iris roti dari bijian utuh, ½ kue
muffin dari bijian utuh, 2-6 biskuit kering atau crackers, ½ cangkir
kacang-kacangan, ⅔ cangkir kacang koro, atau 40 gram mi/pasta
dari bijian utuh.
g. Lemak
Rata-rata kebutuhan lemak dewasa adalah 4½ porsi lemak (14 gram
perporsi) perharinya. Satu porsi lemak sama dengan 80 gram keju, 3
sendok makan kacang tanah atau kenari, 4 sendok makan krim 1
cangkir es krim, ½ buah alpukat, 2 sendok makan selai kacang, 120-
140 gram daging tanpa lemak, 9 kentang goreng, 2 iris cake, 1
sendok makan mayones atau mentega, atau 2 sendok makan saus
salad.
h. Garam
Selama periode nifas, hindari konsumsi garam berlebihan. Hindari
makanan asin seperti kacang asin, keripik kentang atau acar.
i. Cairan
Konsumsi cairan sebanyak 8 gelas per hari. Minum sedikitnya 3 liter
tiap hari. Kebutuhan akan cairan diperoleh dari air putih, sari buah.
susu dan sup.
384
j. Vitamin
Kebutuhan vitamin selama menyusui sangat dibutuhkan. Vitamin
yang diperlukan antara lain:
1) Vitamin A yang berguna bagi kesehatan kulit, kelenjar serta
mata. Vitamin A terdapat dalam telur, hati dan keju. Jumlah
yang dibutuhkan adalah 1,300 mcg.
2) Vitamin B6 membantu penyerapan protein dan meningkatkan
fungsi syaraf. Asupan vitamin B6 sebanyak 2,0 mg per hari.
Vitamin B6 dapat ditemui di daging, hati, padi-padian, kacang
polong dan kentang.
3) Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan. meningkatkan stamina
dan daya tahan tubuh. Terdapat dalam makanan berserat.
kacang-kacanga, minyak nabati dan gandum.
k. Zinc (Seng)
Berfungsi untuk kekebalan tubuh, penyembuhan luka dan
pertumbuhan. Kebutuhan Zinc didapat dalam daging, telur dan
gandum. Enzim dalam pencernaan dan metabolisme memerlukan
seng. Kebutuhan seng setiap hari sekitar 12 mg. Sumber seng
terdapat pada seafood, hati dan daging.
2. Ambulasi
Setelah bersalin, ibu akan merasa lelah. Oleh karena itu. ibu harus
istirahat. Mobilisasi yang dilakukan tergantung pada komplikasi
persalinan, nifas dan sembuhnya luka. Ambulasi dini (early ambulation)
adalah mobilisasi segera setelah ibu melahirkan dengan membimbing ibu
untuk bangun dari tempat tidurnya. Ibu post partum diperbolehkan
bangun dari tempat tidurnya 24-48 jam setelah melahirkan. Anjurkan ibu
untuk memulai mobilisasi dengan miring kanan/ kiri, duduk kemudian
berjalan. Keuntungan ambulasi dini adalah:
a. lbu merasa lebih sehat dan kuat
b. Fungsi usus, sirkulasi, paru-paru dan perkemihan lebih baik
c. Memungkinkan untuk mengajarkan perawatan bayi pada ibu
385
d. Mencegah trombosis pada pembuluh tungkai
e. Sesuai dengan keadaan Indonesia (sosial ekonomis)
Menurut penelitian mobilisasi dini tidak berpengaruh buruk. tidak
menyebabkan perdarahan abnormal, tidak mempengaruhi penyembuhan
luka episiotomi maupun luka di perut, serta tidak memperbesar
kemungkinan prolapsus uteri. Early ambulation tidak dianjurkan pada ibu
post partum dengan penyulit, seperti anemia, penyakit jantung, penyakit
paru-paru, demam, dan sebagainya (Nugroho dkk, 2014).
3. Eliminasi : BAB/BAK
Buang air sendiri sebaiknya dilakukan secepatnya. Miksi normal bila
dapat BAK spontan setiap 3-4 jam. Kesulitan BAK dapat disebabkan
karena springter uretra tertekan oleh kepala janin dan spasme oleh iritasi
muskulo spingter ani selama persalinan. atau dikarenakan oedem
kandung kemih selama persalinan. Lakukan kateterisasi apabila kandung
kemih penuh dan sulit berkemih.
Ibu diharapkan dapat BAB sekitar 3-4 hari post partum. Apabila
mengalami kesulitan BAB/obstipasi. lakukan diet teratur, cukup cairan,
konsumsi makanan berserat, olahraga, berikan obat rangsangan per
oral/per rektal atau lakukan klisma bilamana perlu (Nugroho dkk, 2014).
4. Kebersihan diri dan perineum
Kebersihan diri berguna untuk mengurangi infeksi dan men'ngkatkan
perasaan nyaman. Kebersihan diri meliputi kebersihan tubuh, pakaian.
tempat tidur maupun lingkungan. Beberapa hal yang dapat dilakukan ibu
post partum dalam menjaga kebersihan diri adalah sebagai berikut :
a. Mandi teratur minimal 2 kali sehari
b. Mengganti pakaian dan alas tempat tidur
c. Menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal
d. Melakukan perawatan perineum
e. Mengganti pembalut minimal 2 kali sehari
f. Mencuci tangan setiap membersihkan daerah genetalia (Nugroho
dkk, 2014).
386
5. Istirahat
Ibu nifas memerlukan istirahat yang cukup. istirahat tidur yang
dibutuhkan ibu nifas sekitar 8 jam pada malam hari dan 1 jam pada siang
hari. Hal-hal yang dapat di|akukan ibu dalam memenuhi kebutuhan
istirahatnya antara lain:
a. Anjurkan ibu untuk cukup istirahat
b. Sarankan ibu untuk melakukan kegiatan rumah tangga secara
perlahan
c. Tidur siang atau istirahat saat bayi tidur
Kurang istirahat dapat menyebabkan:
a. Jumlah ASI berkurang
b. Memperlambat proses involusio uteri
c. Menyebabkan depresi dan ketidakmampuan dalam merawat bayi
sendiri (Nugroho dkk, 2014).
6. Seksual
Hubungan seksual dilakukan begitu darah berhenti. Namun demikian
hubungan seksual dilakukan tergantung suami istri tersebut. Selama
periode nifas, hubungan seksual juga dapat berkurang. Hal yang dapat
menyebabkan pola seksual selama nifas berkurang antara lain:
a. Gangguan/ketidaknyamanan fisik
b. Kelelahan
c. Ketidakseimbangan hormon
d. Kecemasan berlebihan
Pada saat melakukan hubungan seksual sebaiknya perhatikan waktu,
penggunaan kontrasepsi, dispareuni. kenikmatan dan kepuasan pasangan
suami istri (Nugroho dkk, 2014).
7. Latihan/senam nifas
Organ-organ tubuh wanita akan kembali seperti semula sekitar 6 minggu.
Oleh karena itu, ibu akan berusaha memulihkan dan mengencangkan
bentuk tubuhnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara latihan senam
nifas. Senam nifas adalah senam yang dilakukan seiak hari pertama
387
melahirkan sampai dengan hari ke sepuluh. Beberapa faktor yang
menentukan kesiapan ibu untuk memulai senam nifas antara lain:
a. Tingkat kebugaran tubuh ibu
b. Riwayat persalinan
c. Kemudahan bayi dalam pemberian asuhan
d. Kesulitan adaptasi post partum
Tujuan senam nifas adalah sebagai berikut:
a. Membantu mempercepat pemulihan kondisi ibu
b. Mempercepat proses involusio uteri
c. Membantu memulihkan dan mengencangkan otot panggul, perut dan
perineum
d. Memperlancar pengeluaran lochea
e. Membantu mengurangi rasa sakit
f. Merelaksasikan otot-otot yang menunjang proses kehamilan dan
persalinan
g. Mengurangi kelainan dan komplikasi masa nifas
Manfaat senam nifas antara lain:
a. Membantu memperbaiki sirkulasi darah
b. Memperbaiki sikap tubuh dan punggung pasca persalinan
c. Memperbaiki otot tonus, pelvis dan peregangan otot abdomen
d. Memperbaiki dan memperkuat otot panggul
e. Membantu ibu lebih relaks dan segar pasca melahirkan
Senam nifas dilakukan pada saat ibu benar-benar pulih dan tidak ada
komplikasi atau penyulit masa nifas atau diantara waktu makan. Sebelum
melakukan senam nifas, persiapan yang dapat dilakukan adalah:
a. Mengenakan baju yang nyaman untuk olahraga
b. Minum banyak air putih
c. Dapat dilakukan di tempat tidur
d. Dapat diiringi musik
e. Perhatikan keadaan ibu (Nugroho dkk, 2014).
388
F. Daftar Pustaka
Nugroho, dkk. 2014. Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas (Askeb 3).
Yogyakarta: Nuha Medika
390
SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP)
TANDA BAHAYA NIFAS
Topik : Asuhan Ibu Nifas
Sub Topik : Tanda Bahaya Nifas
Tanggal : 15 April 2020
Tempat : PMB Siti Rohmani, S.ST
Sasaran : Ny.”T”
A. Tujuan
Setelah mendapatkan penyuluhan ini, diharapkan ibu dapat mengetahui tentang
tanda bahaya pada masa nifas
B. Media : Buku KIA
C. Metode : Ceramah dan Tanya Jawab
D. Langkah-langkah penyuluhan :
No Tahap Waktu Kegiatan
1. Pembukaan 1 menit Mengucapkan salam
Memperkenalkan diri
2. Pelaksanaan dan
penyampaian
materi
3 menit Menjelaskan tanda bahaya pada
masa nifas
3. Diskusi 5 menit Menjawab pertanyaan dari ibu
4. Penutup 1 menit Penyimpulkan hasil penyuluhan
Memberi saran
Mengucapkan saran penutup
E. Materi
Tanda bahaya masa nifas :
1. Perdarahan lewat jalan lahir
2. Keluar cairan berbau dari jalan lahir
3. Bengkak di wajah, tangan dan kaki, atau sakit kepala dan kejang-kejang
4. Demam lebih dari 2 hari
5. Payudara bengkak, merah disertai rasa sakit
391
6. Ibu terlihat sedih, murung dan menangis tanpa sebab (depresi)
F. Daftar Pustaka
Kemenkes RI. 2016. Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta: Kementerian
Kesehatan RI.
393
SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP)
PERAWATAN BAYI DAN ASI EKSKLUSIF
Topik : Asuhan Bayi Baru Lahir
Sub Topik : Perawatan Bayi di Rumah dan ASI Eksklusif
Tanggal : 15 April 2020
Tempat : PMB Siti Rohmani, S.ST
Sasaran : Ny.”T”
A. Tujuan
1. Setelah mendapatkan penyuluhan ini, diharapkan ibu dapat mengetahui
cara merawat bayi di rumah.
2. Setelah mendapatkan penyuluhan ini, diharapkan ibu mengetahui tentang
ASI eksklusif dan cara menyusui
B. Media : Buku KIA
C. Metode : Ceramah dan Tanya Jawab
D. Langkah-langkah penyuluhan :
No Tahap Waktu Kegiatan
1. Pembukaan 1 menit Mengucapkan salam
Memperkenalkan diri
2. Pelaksanaan dan
penyampaian
materi
3 menit Menjelaskan tentang perawatan
bayi, ASI eksklusif dan cara
menyusui
3. Diskusi 5 menit Menjawab pertanyaan dari ibu
4. Penutup 1 menit Penyimpulkan hasil penyuluhan
Memberi saran
Mengucapkan saran penutup
E. Materi
1. Perawatan Bayi Baru Lahir
a. Perawatan Tali Pusat
1) Tujuan perawatan tali pusat
a) Untuk mempercepat pelepasan tali pusat
394
b) Untuk mencegah terjadinya infeksi
2) Cara perawatan tali pusat
a) Selalu cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir
sebelum dan sesudah memegang bayi
b) Jangan memberikan apapun pada tali pusat
c) Rawat tali pusat terbuka dan kering
d) Bila tali pusat kotor atau basah, cuci dengan air bersih dan
sabun mandi dan keringkan dengan kain bersih
b. Memandikan Bayi
1) Basuh lembut wajah bayi dengan kapas yang dilembabkan dengan
air hangat lalu keringkan dengan lembut
2) Basuh rambut bayi dengan tangan yang telah diberi shampo bayi,
pijat lembut seluruh kepala bayi
3) Buka pakaian bayi, bersihkan bokong bayi sebelum meletakkan
kedalam bak mandi
4) Bersihkan badan bayi dengan menggunakan washlap dan sabun
5) Biarkan bayi menikmati air mandi hangat untuk beberapa saat
6) Keringkan badan bayi yang basah
7) Pakaikan baju dan popok yang bersih
c. Menjemur Bayi
Jemur bayi di bawah sinar matahari pagi selama 10-15 menit, jemur
bayi dalam keadaan telanjang.
d. Mencegah Hipotermi
Cegah hipotermi dengan menggantikan popok bayi bila basah, jaga
kehangatan badan bayi, jangan memandikan bayi dengan air dingin,
tutupi kepala bayi dengan topi.
2. ASI Eksklusif
Pemberian ASI sejak awal pada bayi sangatlah penting, karena ASI
merupakan satu-satunya makanan dan minuman yang baik untuk bayi
dalam masa 6 bulan pertama kehidupannya.
395
a. Pengertian
ASI eksklusif adalah pemberian ASI selama 6 bulan tanpa pemberian
makanan dan minuman lainnya.
b. Manfaat pemberian ASI eksklusif
1) Sehat, praktis dan tidak butuh biaya
2) Meningkatkan kekebalan alamiah pada bayi
3) Mencegah perdarahan pada ibu nifas
4) Menjalin kasih sayang ibu dan bayi
5) Mencegah kanker payudara
3. Teknik Menyusui yang Benar
a. Sebelum menyusui keluarkan sedikit ASI kemudian oleskan pada
puting susu dan aerola.
b. Bayi diletakkan menghadap perut ibu/payudara, usahakan perut ibu
dan bayi saling menempel.
c. Payudara dipegang dengan cara ibu jari dan jali telunjuk membentuk
huruf C dan cari yang lain dibawahnya, dan jangan menekan puting
susu atau aerolanya saja.
d. Bayi diberi rangsangan untuk membuka mulut dengan cara puting susu
ibu diletakkan di ujung bibir bayi.
e. Usahakan sebagian besar aerola dapat masuk kedalam mulut bayi.
f. Setelah selesai menyusui, ASI dikeluarkan sedikit kemudian oleskan
kembali pada puting dan sekitarnya.
g. Menyendawakan bayi.
F. Daftar Pustaka
Kemenkes RI. 2016. Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta: Kementerian
Kesehatan RI.
398
SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP)
TANDA BAHAYA PADA BAYI BARU LAHIR
Topik : Asuhan Bayi Baru Lahir
Sub Topik : Tanda Bahaya pada Bayi Baru Lahir
Tanggal : 15 April 2020
Tempat : PMB Siti Rohmani, S.ST
Sasaran : Ny.”T”
A. Tujuan
Setelah mendapatkan penyuluhan ini, diharapkan ibu dapat mengetahui tanda
bahaya pada bayi baru lahir
B. Media : Buku KIA
C. Metode : Ceramah dan Tanya Jawab
D. Langkah-langkah penyuluhan :
No Tahap Waktu Kegiatan
1. Pembukaan 1 menit Mengucapkan salam
Memperkenalkan diri
2. Pelaksanaan dan
penyampaian
materi
3 menit Menjelaskan tentang tanda bahaya
pada bayi baru lahir
3. Diskusi 5 menit Menjawab pertanyaan dari ibu
4. Penutup 1 menit Penyimpulkan hasil penyuluhan
Memberi saran
Mengucapkan saran penutup
E. Materi
Tanda bahaya pada bayi baru lahir :
a. Tidak mau menyusu
b. Kejang-kejang
c. Lemah
d. Sesak nafas (lebih besar atau sama dengan 60 kali/menit), tarikan dinding
dada bagian bawah ke dalam
399
e. Bayi merintih atau menangis terus menerus
f. Tali pusar kemerahan sampai dinding perut, berbau atau bernanah
g. Demam/panas tinggi
h. Mata bayi bernanah
i. Diare/buang air besar cair lebih dari 3 kali sehari
j. Kulit dan mata bayi kuning
k. Tinja bayi saat buang air besar bewarna pucat
F. Daftar Pustaka
Kemenkes RI. 2016. Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta: Kementerian
Kesehatan RI.
401
SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP)
KELUARGA BERENCANA (KB)
Topik : Asuhan Keluarga Berencana
Sub Topik : Keluarga Berencana (KB)
Tanggal : 14 Mei 2020
Tempat : PMB Siti Rohmani, S.ST
Sasaran : Ny.”T”
A. Tujuan
Setelah mendapatkan penyuluhan ini, diharapkan ibu dapat mengetahui tentang
macam-macam KB, kelebihan dan kekurangannya serta mampu menentukan
pilihan KB untuk dirinya.
B. Media : Leaflet
C. Metode : Ceramah dan Tanya Jawab
D. Langkah-langkah penyuluhan :
No Tahap Waktu Kegiatan
1. Pembukaan 1 menit Mengucapkan salam
Memperkenalkan diri
2. Pelaksanaan dan
penyampaian
materi
5 menit Menjelaskan tentang macam-
macam KB, kelebihan dan
kekurangannya
3. Diskusi 5 menit Menjawab pertanyaan dari ibu
4. Penutup 1 menit Penyimpulkan hasil penyuluhan
Memberi saran
Mengucapkan saran penutup
E. Materi
1. Pengertian
Keluarga berencana merupakan usaha menjarangkan atau merencanakan
jumlah dan jarak kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi
(Sulistyawati, 2013)
402
2. Macam-macam KB
a. Metode Amenrrhea Laktasi (MAL)
Metode Amenorrhea Laktasi (MAL) adalah kontrasepsi yang
mengandalkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara ekslusif, artinya
ASI hanya diberikan kepada bayinya tanpa makanan atau minuman
tambahan hingga usia 6 bulan.
Cara kerja : Penundaan atau penekanan ovulasi
Keuntungan : Tidak menggangggu saat berhubungan seksual,
segera efektif bila digunakan dengan benar, tidak
ada efek samping secara sistemik, tidak perlu
pengawasan medis, tidak perlu obat atau alat, tanpa
biaya
Kerugian : Perlu persiapan dan perawatan sejak awal
kehamilan agar segera menyusui dalam 30 menit
pascapersalinan, sulit dilaksanakan karena kondisi
sosial, efektifitas tinggi hanya sampai usia 6 bulan
atau kembalinya haid (Mulyani dan Rinawati,
2013).
b. Kondom
Kondom merupakan selubung atau sarung karet yang terbuat dari
berbagai bahan diantaranya karet (lateks), plastik (vinil) atau bahan
alami (produksi hewani) yang dipasang pada penis untu menampung
sperma ketika seorang pria mencapai ejakulasi saat berhubungan
seksual.
Cara kerja : mencegah sperma masuk ke saluran reproduksi
wanita dan sebagai pelindung terhadap infeksi atau
transmisi mikroorganisme penyebab PMS.
Keuntungan : Murah dan dapat dibeli secara umum, tidak
mempunyai pengaruh sistemik, tidak mengganggu
produksi ASI, tidak perlu resep dokter atau
403
pemeriksaan kesehatan khusus, efektif bila
pemakaian benar.
Kerugian : Cara penggunaan sangat mempengaruhi
keberhasilan kontrasepsi, agak mengganggu
hubungan seksual (mengurangi sentuhan langsung),
pada beberapa klien bisa menyebabkan kesulitan
untuk mempertahan ereksi, harus selalu tersedia
setiap kali berhubungan seksual (Mulyani dan
Rinawati, 2013).
c. Mini Pil
Mini pil adalah pil KB yang hanya mengandung hormon progesteron
dalam dosis rendah. Mini pil atau pil progestin disebut juga pil
menyusui.
Cara kerja : menghambat ovulasi, mencegah implantasi,
mengentalkan lendir serviks sehingga menghambat
penetrasi sperma, dan mengubah motilitas tuba
sehingga transportasi sperma menjadi terganggu.
Keuntungan : Cocok sebagai alat kontrasepsi untuk perempuan
yang sedang menyusui, sangat efektif untuk masa
laktasi, tidak menurunkan produksi ASI, tidak
mengganggu hubungan seksual, kesuburan cepat
kembali, cocok untuk penderita diabetes melitus,
dapat mengurangi dismiorhea.
Kerugian : Harus selalu tersedia, efektifitas berkurang apabila
menyusuia juga berkurang, penggunaan bersamaan
dengan obat tuberkulosis atau epilepsi akan
mengakibatkan efektifitas menjadi rendah, harus
diminum setiap hari pada waktu yang sama, tidak
melindungi dari penyakit menular seksual, tidak
melindungi dari penyakit kista ovarium bagi wanita
404
yang pernah mengalami kehamilan ektopik (Mulyani
dan Rinawati, 2013).
d. Suntik 3 bulan
Suntik tribulan merupakan metode kontrasepsi yang diberikan secara
intramuscular setiap tiga bulan.
Cara kerja : menghalangi terjadinya ovulasi dengan jalan
menekan pembentukan releasing factor dari
hipotalamus, leher serviks bertambah kental sehingga
menghambat penetrasi sperma melalui serviks uteri,
menghambat implantasi ovum dalam endometrium
Keuntungan : Efektifitas tinggi, sederhana pemakaiannya, injeksi
hanya perlu 4 kali dalam setahun, cocok untuk ibu
menyusui, dapat mencegah kanker endometrium,
kehamilan ektopik, serta beberapa penyebab penyakit
akibat radang panggul
Kerugian : Gangguan haid, timbul jerawat, berat badan
bertambah, pusing dan sakit kepala,ras nyeri pada
daerah suntikan (Mulyani dan Rinawati, 2013).
e. Implant
Kontrasepsi implant adalah alat kontrasepsi yang dipasang dibawah
kulit. Implant adalah suatu alat kontrasepsi yang mengandung
levonorgetrel yang dibungkus dalam kapsul silastic
silicon(polydimethylsiloxane) dan dipasang dibawah kulit (Mulyani
dan Rinawati, 2013).
Cara kerja : lendir serviks menjadi kental, mengganggu proses
pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi
implantasi, mengurangi transportasi sperma, menekan
ovulasi
Keuntungan :Perlindungan jangka panjang (3 tahun),
pengembalian tingkat kesuburan cepat setelah
405
pencabutan, tidak mengganggu aktivitas seksual, tidak
mengganggu produksi ASI
Kerugian :Nyeri kepala, nyeri payudara, peningkatan/penurunan
berat badan, mual, pusing, membutuhkan tindakan
pembedahan minor untuk insersi dan pencabutan,
tidak bisa menghentikan sendiri pemakaian
kontrasepsi tetapi harus datang ke klinik untuk
pencabutan (Sulistyawati, 2013).
f. IUD
IUD singkatan dari Intra Uterine Device yang merupakan alat
kontrasepsi paling banyak digunakan, karena dianggap sangat efektif
dalam mencegah kehamilan dan memiliki manfaat yang relatif
banyak dibanding alat kontrasepsi lainnya. Diantaranya tidak
mengganggu saat coitus (hubungan badan), dapat digunakan sampai
menopause dan setelah IUD dikeluarkan dari rahim, bisa dengan
mudah subur.
Cara kerja : mencegah sperma bertemu sel telur, mencegah
implantasi atau tertanamnya sel telur dalam rahim
Keuntungan : Perlindungan jangka panjang (sampai 10 tahun),
efektif segera setelah pemasangan, tidak tergantung
pada daya ingat, tidak mempengaruhi hubungan
seksual, tidak ada interaksi obat-obatan, membantu
mencegah kehamilan di luar kandungan
Kerugian : Memerlukan pemeriksaan dalam, perdarahan diantara
haid, kram perut setelah pemasangan dalam beberapa
hari, meningkatkan risiko radang panggul (Mulyani dan
Rinawati, 2013).
g. Steril (kontrasepsi mantap)
Kontrasepsi mantap merupakan salah satu metode kontrasepsi yang
dilakukan dengan cara mengikat atau memotong saluran telur (pada
perempuan) dan saluran sperma (pada laki-laki). Karena sifatnya
406
yang permanen, kontrasepsi ini hanya diperkenankan bagi mereka
yang sudah mantab memutuskan untuk tidak lagi mempunyai anak
(Mulyani dan Rinawati, 2013). Kontrasepsi ini dibagi menjadi 2
yaitu Metode Operatf Wanita (MOW) dan Metode Operatif Pria
(MOP) :
1) Metode Operatif Wanita (MOW)/Tubektomi
Tubektomi adalah setiap tindakan pada kedua saluran telur
wanita yang mengakibatkan orang yang bersangkutan tidak akan
mendapatkan keturunan lagi (Mulyani dan Rinawati, 2013).
Cara kerja : Cara kerja tubektomi atau ligasi tuba yaitu dengan
mengonklusi tuba falopii (mengikat dan memotong
atau memasang cincin) sehingga sperma tidak dapat
bertemu dengan ovum (Mulyani dan Rinawati,
2013).
Keuntungan : Efektifitas tinggi, permanen, efektif dengan segera
(Subekti, 2013).
Kerugian : Melibatkan prosedur pembedahan dan anastesi,
tidak mudah kembali subur, jika ada kegagalan
metode maka ada risiko tinggi kehamilan ektopik
(Subekti, 2013).
2) Metode Operatif Pria (MOP)/Vasektomi
Vasektomi adalah pemotongan vas deferens, yang merupakan
saluran yang mengangkut sperma dari epididimis di dalam testis
ke vesikula seminalis. Dengan memotong vas deferens, sperma
tidak mampu diejakulasikan dan pria akan menjadi tidak subur
setelah vas deferens bersih dari sperm, yang memakan waktu
sekitar tiga bulan (Subekti, 2013).
Keuntungan : metode permanen, efektifitas tinggi,
menghilangkan kecemasan akan terjadi kehamilan
yang tidak direncanakan, prosedur aman dan
sederhana (Subekti, 2013).
407
Kerugian : diperlukan kontrasepsi alternatif sampai didapat
dua kali hitung sperma bersih secara berurutan,
diperlukan prosedur pembedahan, dibutuhkan
anastesi lokal atau anastesi umum, tidak mudah
untuk kembali subur (Subekti, 2013).
F. Daftar Pustaka
Mulyani, N.S., dan M. Rinawati. 2013. Keluarga Berencana dan Alat
Kontrasepsi. Yogyakarta: Nuha Medika.
Subekti, N.B. 2013. Buku Saku Kontrasepsi & Kesehatan Seksual
Reproduktif. Jakarta: EGC.