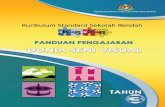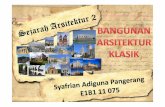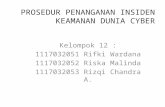Kiri Islam dan Perdamaian Dunia
-
Upload
aamgituloh -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Kiri Islam dan Perdamaian Dunia
Kiri Islam dan Perdamaian Dunia
(Konsep Perdamaian Hassan Hanafi)
Disusun untuk materi kajian pada mata kuliahyang diampu oleh Dr. Muti'ullah, MA
Disusun Oleh:
ABAZ ZAHROTIEN
1320512095
STUDI AGAMA DAN RESOLUSI KONFLIKPRODI AGAMA DAN FILSAFAT
Kiri Islam dan Perdamaian Dunia
(Konsep Perdamaian Hassan Hanafi)
Framing dan prejustice dunia internasional terhadap
Islam dalam dua dasawarsa terakhir mengalineasikan
objektivitas dan mengedepankan penilaian negatif.
Stereotyping semacam ini tidak hanya terjadi pada
kalangan tertentu yang anti terhadap Islam,melainkan
telah menjalar pada masyarakat umum dengan satu konsep
pemikiran yang sama, yakni Islam adalah agama
kekerasan.
Western stereotypes of Islam as a bellicose ideology and Muslims as
intractable aggressors arose largely during the period of the Crusades,
although attitudes contributing to this view circulated much earlier in
Christian Europe. 1
Norman Daniel dalam mendeskripsikan tentang cara
pandang Islam tersebut diatas bukan hanya sekedar
penjelasan berdasar asumsi, melainkan mengumpulkan
fakta-fakta dan mengujinya dengan cara pandang publik.
Pada intinya bahwa Islam di mata dunia sudah dalam
kondisi nirperdamaian. Islam merupakan sebuah agama
1 Norman Daniel’s, Islam and the West: The Making of an Image, Edinburgh:Edinburgh University Press, 1960, hal 127.
yang tidak mendukung terciptanya perdamaian dunia dan
memaksakan perdamaian berdasarkan kebenaran yang
dianutnya.
Asumsi publik terhadap laku kekerasan yang
diajarkan oleh agama Islam semakin diperkuat dengan
gerakan terorisme di dunia yang semakin menguat, bahkan
sudah mencapai level perang, khususnya di Timur Tengah.
Islam tidak lagi memiliki citra agama damai dengan
perwujudan nilai-nilai kekerasan agama yang
dimanifestasikan oleh kelompok-kelompok tertentu.
Peperangan atas nama agama yang terjadi, atau
spesifiknya tindakan teror atas nama agama yang
dilakukan oleh kelompok Islam radikal ternyata cukup
mampu mengubah wajah Islam secara menyeluruh. Dunia
memandang bahwa Islam merupakan bentuk agama intoleran
yang tidak memiliki kesadaran tentang arti penting
perdamaian sesama manusia.
Melihat penjelasan Norman Daniels tersebut,
sebenarnya tidak sejak dua dasawarsa terakhir, citra
Islam sebagai agama militer telah terbangun sejak
perang salib (crussade), dimana saat itu, Islam dinilai
berperan besar dalam menciptakan perang antar agama.
Munculnya gerakan terorisme yang dimulai pada awal abad
21 ini, merupakan penguat sekaligus dianggap sebagai
momen revivalis bagi kelompok Islam garis keras.
Padahal menilik sejarah agama-agama di dunia,
nyaris semua agama tidak ada yang lepas dari sejarah
kekerasan dan peperangan. Semua itu telah dilewati oleh
agama-agama yang ada untuk mempertahankan eksistensi
agama itu sendiri atau memperluas wilayah pengaruh
agama sehingga menimbulkan benturan. Namun, citra
peperangan lebih lekat pada Islam ketimbang agama yang
lain.
We know that all religious traditions have been implicated in
promoting violence over the centuries. Indeed, some people insist that
including religious individuals in the process of conflict resolution is like
inviting foxes into the hen house. Religion and Peacebuilding begs to
differ. It argues that we need to pay attention to religion when trying to
make sense of human activities, and recognize that religious traditions
have the resources to help us promote peace2.
Harold Coward dan Gordon Smith, sepertinya cukup
objektif dalam hal ini, mereka menempatkan semua agama
memiliki sejarah kekerasan tanpa kemudian
menyetereotipkan satu agama dan mengabaikan klaim pada
yang lain. Mereka menyadari bahwa perang dan kekerasan
tidak pernah lepas dari sejarah agama-agama sejak zaman
dahulu. Kontribusi agama-agama pada peperangan dan
jihad tidak terelakkan ketika meninjau sejarah seluruh
agama-agama yang ada. Mereka memiliki peran penting
2 Harlod Coward and Godon S. Smith (eds), Religion and Peacebuilding, State University of New York, 2004, hal. vii
dalam menciptakan peperangan atas nama agama, tentu
juga dengan konsep perdamaian. Termasuk diantaranya
Islam sebagai agama yang juga memiliki riwayat
peperangan.
Dalam kamus dunia internasional, menilik Islam
lebih populer nama-nama seperti Sayyid Qutb, Abu A’la
Al Maududi, Al Qaeda, Osama bin Laden, serta tokoh-
tokoh gerakan Islam radikal ketimbang nama-nama Chiragh
‘Ali, M. Shaltut dan Yusuf Qardhawi. Termasuk nama
Hassan Hanafi, seorang pemikir jebolan Sorobne
University ini.
Sumbangsih intelektual muslim kepada dunia
internasional pada dasarnya sangat besar. Ini terlihat
dari aspek historis yang mencantumkan nama intelektual-
intelektual muslim pada berbagai bidang kehidupan.
Padahal, mengabaikan komplektisitas pola-pola
kebudayaan yang membentuk peradaban Timur Tengah sejak
abad-abad pra-Kristen serta perkembangan fenomenologis
ilmu pengetahuan dan institusi-institusi pendidikan
Islam selama berabad-abad, sama halnya dengan
mengabaikan asas-asas pokok tradisi Barat yang kini
menjadi gaya hidup.
Ketika Eropa tengah berbenah untuk mengajari tata
cara menulis dan administratif terhadap masyarakatnya,
dunia intelektual Islam telah sampai pada memelihara,
memodifikasi dan menyempurnakan kebudayaan-kebudayaan
klasik melalui sekolah-sekolah tinggi dan pusat riset
yang telah maju dibawah para penguasa yang memiliki
wawasan keilmuan. Kemudian, hasil dari usaha kreatif
dan jenius tersebut telah menjangkau wilayah Latin
Barat melalui penerjemahan versi bahasa Arab atas
karya-karya klasik maupun tulisan-tulisan cendekiawan
Muslim tentang kedokteran, filsafat, geografi, sejarah,
teknologi, pedagogi dan disiplin ilmu lainnya3.
Dalam perkembangan kekinian, dunia intelektual
Islam tidak berarti mati setelah fatwa penutupan pintu
ijtihad oleh ulama pada akhir masa kejayaan Islam.
Tetapi, ia tetap mengambil posisi sebagai salah satu
sumber pengetahuan dengan peningkatan dunia penelitian,
pengkajian dan sumbangsih lainnya untuk kepentingan
umat manusia. Tokoh-tokoh ilmuwan dari kalangan Muslim
bermunculan di dunia untuk mendarmabhaktikan
pengetahuannya bagi kemanfaatan seluruh alam raya.
Hassan Hanafi dan Kiri Islam
Nama Hassan Hanafi lebih populer di kalangan kaum
pergerakan, khususnya pergerakan Islam Kiri dengan
teori-teori hasil pemikirannya yang dapat dikategorikan3 Mehdi Nakosteen, History of Islamic Origins of Western Education. A.D, 800-1350 with an Introduction to Medieval Muslim Education, University of Coloardo Press, Coloardo, 1954, hal. vii
revolusioner. Ia mencoba melepaskan pakem pemikiran
klasik dan menempatkan model pemikiran baru yang lebih
efektif sebagai way of life. Pemikiran tentang Kiri Islam,
Oksidentalisme, Turats dan Tajdid mewarnai khazanah
keilmuan dalam Islam hasil olah otak akademisi asal
Mesir ini.
Dr. Hassan Hanafi sadar bahwa dalam beberapa abad
terakhir, Islam tidak lagi muncul sebagai salah satu
kandang ilmu pengetahuan. Tokoh-tokoh yang muncul dalam
Islam bukan lagi merupakan tokoh membawa khazanah
keilmuan baru untuk peningkatan kemajuan umat manusia.
Islam tertinggal jauh dengan Barat dalam banyak sisi
yang pada periode sebelumnya Islam pernah menempati
posisi puncak. Kesadaran itu, oleh Hanafi dianalisis
mendalam untuk melihat penyebab dan persoalan mendasar
yang menyebabkannya.
Analisis terhadap penyebab munculnya kemunduran
Islam tersebut pada akhirnya mendapatkan solusi dengan
pemikirannya. Ia yakin bahwa Islam akan terlepas dari
belenggu kemundurannya dengan solusi yang ia tawarkan
secara imiah melalu karya-karyanya. Salah satu tawaran
yang cukup membuat perdebatan dalam Islam sendiri
adalah tentang konsepsi Kiri Islam (Islamic Left). Ia
mengkomparasikan antara nilai-nilai kekirian dengan
basis teologis yang menekankan perlawanan terhadap
segala bentuk kemunduran. Bagai kalangan tertentu, ini
bukan merupakan hal yang baru, tetapi Hanafi mampu
meletakan konsepsinya ini pada dasar kerangka pemikiran
yang kuat antara modernisme dan postmodernisme.
Sejak kemunculan Islam pada awal abad ketujuh di
semenanjung Arabia, umat manusia telah mengalami banyak
perkembangan. Mereka inilah yang menolak relevansi
agama dengan zaman ini. Kita berada di abad sains dan
teknologi, abad penelitian, bukan abad iman. Meskipun
dalam berbagai kasus tidak tepat, dalam pandangan ini,
iman melahirkan kemandekan menolak ijtihad dan bersifat
dogmatis, oleh karena itu tidak relevan dengan abad
ini. Dalam sejarah Islam hingga abad ketiga belas,
pertentangan antara iman dan akal juga pernah terjadi.
Hal ini mencuat ke permukaan ketika pintu ijtihad telah
ditutup dan taqlid ditekankan4
Dasar teologis yang dilandasakan oleh Hanafi dalam
ajaran kirinya adalah teologisnya itu sendiri (tahuid).
Nilai teologis dinilai merupakan basis dari kemajuan
Islam pada abad awal dan masa berjayanya di abad
pertengahan. Namun berbeda pada zaman itu yang
menitikberatkan aspek tahuid pada sisi ketuhanan saja,
Hanafi memperkenalkan tauhid dengan membagi dua aspek,
yakni aspek ketuhanan dan kemanusiaan. Ia menafsirkan
4 Asghar Ali Engineer, Islam and Its Relevance to Our Age, LKiS Yogyakarta,2007, hal. 45
tauhid sebagai sebuah konsep penyatuan antara aspek-
aspek kemanusiaan dan aspek-aspek ketuhanan.
Korelasi antara manusia dan tuhan dalam pemikiran
Hanafi akan mengantarkan pada analisis keyakinan
terhadap Tuhan yang Esa (dasar tahuid), lalu keyakinan
bahwa dalam menciptakan manusia, Tuhan tidak pernah
melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras,
warna kulit, tingkat kekayaan dan chauvinistik lainnya.
Hanafi meyakini dengan tidak adanya diskriminasi Tuhan
terhadap manusia merupakan konsepsi tahuid yang utuh
dan disandingkan dengan alam raya yang menjadi tempat
tinggal manusia.
Dari dasar ini, Hanafi meyakini bahwa tindakan
manusia yang melakukan diskriminasi terhadap manusia
yang lain adalah tindakan yang tidak dibenarkan dalam
konsep teologisnya. Bahwa, tindakan tersebut merupakan
aspek yang harus dilawan karena bertentangan dengan
nilai dasar tauhid. Simpulannya, Hanafi meyakini bahwa
Islam dalam kerangka teologis sudah menjamin kebebasan
manusia dari segala bentuk diskriminasi, kolonialisasi
dan imperialisasi oleh manusia yang lainnya.
Dari logika dasar Kiri Islam yang dibangun Hanafi
tersebut, juga menjadi alasan kuat mengapa Hanafi
enggan disandingkan dengan Karl Marx dan Engels dalam
konsepsi kekiriannya. Keduanya memiliki kesamaan spirit
yakni anti terhadap segala bentuk penindasan terhadap
manusia, namun kerangka dasar yang melingkupi gerakan
Marx dan Hanafi memiliki perbedaan yang menonjol.
Ketika Marx memilih konsep anti terhadap agama
(atheisme), maka Hanafi justru menempatkan agama
(tauhid) sebagi landasan dasarnya.
Tahuid dalam pengertian Hanafi diatas juga
memberikan gambaran bahwa Islam merupakan agama yang
bersifat revolusioner. Ia tidak hanya agama yang
mengedepankan nilai transendental, tetapi juga membawa
misi humanisme. Kemanusiaan yang diartikan dalam
kerangka kebersamaan dengan tidak adanya dominasi
antara satu dengan yang lainnya. Hanafi menolak cara
pandang terdahulu yang hanya menitikberatkan sisi
teol6gis dalam Islam dan mengabaikan sisi humanis.
Termasuk kritik kerasnya terhadap sufisme.
Sebagai agama humanis, Islam memiliki sifat
revolusioner yang menentang keras tindak dominatif
antara satu manusia dengan manusia yang lainnya.
Pembedaan dan kolonialisasi juga merupakan kejahatan
tahuid (teologis) karena mengabaikan nilai dasar
tahuid, yakni kesamaan dan kebersamaan manusia
dihadapan Tuhan. Menurut Hanafi, tindakan dominasi
antara manusia adalah hal yang harus dilakukan
perlawanan sehingga tercipta tatanan sesuai dengan
tujuan agama dalam kacamata humanisme, yakni tatanan
sosial yang setara tanpa pembedaan dan dominasi.
Dalam pemahaman tafsir teks suci, hermeneutika bagi
Hanafi bukan hanya ilmu interpretasi, yakni suatu teori
pemahaman, tetapi juga berarti ilmu yang menjelaskan
penerimaan wahyu sejak dari tingkat perkataan sampai
ketingkat dunia. Ilmu tentang proses wahyu dari huruf
sampai kenyataan, dari logos sampai praksis juga dari
transformasi wahyu dari Pikiran Tuhan kepada kehidupan
manusia. Proses pemahaman hanya menduduki tempat kedua
setelah kritik kesejarahan, yang menjamin keaslian
kitab suci dalam sejarah. Cara pandang tersebut membawa
Hanafi pada pola hermeneutika teks suci dan ajaran
Islam memiliki ciri khusus dibanding penafsir lainnya,
termasuk dalam menafsirkan ketauhidan5.
Sikap Hanafi terhadap kolonialisme sangat keras. Ia
mengkategorikan kolonialisme dalam tindak kejahatan
besar. Tindak perlawanan terhadap aksi kolonialisme
merupakan salah satu bentuk ibadah karena bagian dari
pengejawantahan konsep tauhid. Menghapus kolonialisme
dengan perlawanan juga merupakan tanggungjawab umat
Islam sebagai tanggungjawab yang melekat karena tahuid
merupakan hal yang melekat bagi orang Islam yang
beriman.
5 Hassan Hanafi, Religious Dialogue and Revolution, Anglo EgyptianBookshop, Kairo, 1994, hal. 1
Terkait dengan kolonialisme, Hanafi menggunakan
definisi umum, yakni tindak penjajahan satu negara
dengan negara yang lain. Namun dalam hal ini, Hanafi
lebih melekatkan kolonialisme itu terhadap negara-
negara Barat yang melakukan penjajahan terhadap bangsa
non-Barat. Pelekatan itu memiliki latar belakang
historis dilihat dari permusuhan Barat dengan dunia
Arab yang dimulai sejak konfrontasi crussade (perang
salib) hingga saat ini.
Dalam hal kolonialisme, Hanafi juga mengkategorikan
dalam dua bentuk, yakni kolonialisme fisik dan
kolonialisme kultural. Kolonialisme fisik menurutnya
sudah dilakukan pada zaman abad 19 dan 20 dimana
penjajahan Barat terhadap dunia non-Barat sangat
kental. Saat ini sudah mengalami pergeseran sistem
kolonialisme, menjadi kolonialisme kultural. Hanafi
memandang bahwa ancaman yang kedua merupakan ancaman
serius bagi dunia Islam dan harus dilakukan langkah
antisipasi dan perlawanan.
Istilah Barat berkonotasi politis dan diposisikan
berhadapan dengan Timur dari segi politik dan
pemikiran. Barat adalah ilmuwan dan Timur adalah
seniman. Burung Pipit dari Timur dan Kegelapan di
Barat. TImur adalah Timur dan Barat adalah Barat.
Keduanya tidak akan pernah bertemu terutama jika
pendekatan yang dipakai adalah sisa-sisa teori rasialis
dengan berbagai macam bentuknya6.
Program Barat pada sistem kolonialisme kultural ini
terlihat dari Barat yang mencoba melakukan pendirian
'Museum Kebudayaan' bagi bangsa Non-Barat. Barat
menilai bahwa kultur dan budaya non-Barat harus segera
dihanguskan dan dikandangkan pada museum tersebut, dan
budaya Barat menempati posisi kekosongan tersebut.
Setelah Timur lengah dengan budaya yang dikosongkan,
daya kreatif berkurang selanjutnya setelah dikandangkan
budaya itu, Barat akan melakukan pembudayaan dengan
basis Barat yang pada akhirnya menjadi kiblat dimana
Timur akan berubah menjadi bagian dari Barat dalam
berbagai hal.
Hanafi sangat menyayangkan, dunia Timur justru
tidak memiliki kesadaran sampai ke arah sana. Timur
melihat Barat saat ini sebagai kiblat dan tren yang
harus diikuti. Dalam jangka panjang, kebudayaan Timur
tanpa diekspansi akan terkikis dengan sendirinya karena
Barat menawarkan konsep budaya yang jauh lebih diminati
kalangan muda. Pada akhirnya, budaya Timur tersebut
akan mati perlahan. Identitas keTimuran menghilang dan
justru bangsa Timur merasa bangga setelah mampu menjadi
'Barat'.
6 Hassan Hanafi, Muqaddimah fi 'Ilm al Istigrab, Jakarta, Paramadina, 1999, hal. 128
Meski demikian, Hanafi masih menaruh tanggapan
positif terhadap serangan budaya Barat yang menjamur ke
dunia Timur. Bahkan, Islam tidak melakukan pengecaman
terhadap budaya apapun yang dapat diakulturasikan,
termasuk budaya Barat. Untuk itu, ia menekankan perlu
adanya filterisasi kebudayaan. Mana yang dapat
dilakukan sistem akulturatif, dan pada bagian mana yang
harus benar-benar ditinggalkan.
Tidak hanya dunia Barat, Hanafi dengan tegas juga
menyebut Marximisme bagian dari Barat. Ia melihat bahwa
kendati Marximisme adalah antitesis dari kebudayaan
Barat secara umum, namun keberadaan warisan Karl Marx
ini tidak dapat diterima kalangan Islam. Hanafi melihat
Marx sebagai representasi Barat Kiri telah berhasil
masuk pada pergerakan kaum buruh untuk menghilangkan
pertentangan kelas yang terjadi di Barat. Tetapi,
Hanafi tidak serta merta meninggalkan Das Kapital, ia
merupakan satu instrumen yang sama dalam penolakan
kolonialisme dan imperialisme. Dan disini Hanafi
terjebak pada pemikiran yang justru melihat keduanya
dari perbedaan sisi filosofis historis ketimbang
mencari spirit persamaan diantara keduanya.
Konsep Kiri Islam yang dibangun oleh Hanafi bukan
berarti tanpa pertentangan, ia acapkali mendapat
tudingan sebagai pencetus simbol kekafiran dengan
menafaatkan Islam dalam kepentingan kemanusiaan.
Semangat untuk melakukan penolakan terhadap
kolonialisme dan imperialisme adalah semangat
melepaskan pembebasan, demokrasi dan perjuangan dalam
bentuk apapun lebih didasari pencampuradukkan antara
ajaran sosialis-marxis Karl Mark ketimbang sebagai
sebuah pemikiran baru dalam dunia keislaman itu
sendiri.
Padahal, konsep Kiri Islam Hassan Hanafi yang
menentang segala bentuk imperialisme dan kolonialisme
merupakan respon dari tantangan Barat dengan berbagai
rekayasa tatanan. Ia muncul dari Islam sebagai sebuah
disiplin ilmu pengembangan konsepsi tauhid. Pemahaman
yang keliru terhadap konsep Kiri Islam Hanafi kemudian
melekatkan nama Hanafi sejajar dengan para Marxian.
Perdamaian Kiri Islam
Kiri Islam yang ditawarkan Hanafi diyakini mampu
menjadi solusi atas berbagai persoalan kemunduran
Islam. Semangat revolusioner yang diangkut dalam Al
Yassar Al Islam-nya adalah upaya untuk menghilangkan
segala bentuk kolonialisme dan imperialisme dengan
berbagai konsep penjajahan. Tentu tidak serta
menghasilkan kedamaian secara instan. Sebagaimana
konsep perdamaian lainnya, ia membutuhkan proses dari
tahapan pembelajaran, konsolidasi sampai munculnya
konflik turunan sebagai dampak dari perdamaian itu
sendiri.
Terkait dengan perdamaian itu sendiri, Johan
Galtung mempunyai konsep perdamaian yang dibagi dalam
tiga cabang, yakni empirisisme, kritis dan konstruktif.
Pembagian ini merupakan cara untuk mempermudah memahami
bagamimana Al Yassar Al Islam mampu membawa perdamaian,
bahwa pemikiran Hassan Hanafi tentang Kiri Islamnya
menjadi resolusi untuk mencapai perdamaian dunia tanpa
adanya diskriminasi.
Studi perdamaian empiris, didasarkan pada
perbandingan sistematis antara teori dan realitas
empiris (data), dengan merevisi teori jika tidak sesuai
data. Studi perdamaian kritis, didasarkan pada
perbandingan sistematis antara realitas empiris (data)
dengan nilai-nilai, dengan usaha (kata-kata maupun
tindakan), untuk mengubah realitas jika realitas tidak
sesuai dengan nilai dan studi perdamaian konstruktif,
didasarkan pada perbandingan sistematis antara teori
dengan nilai-nilai, dengan berusaha menyesuaikan teori
dengan nilai, sehingga menghasilkan visi realitas baru.
Sesuai dengan pembagian Galtung, teori Kiri Islam
merupakan salah satu jenis dari studi perdamaian
kritis. Ia mencoba membandingkan secara sistematis
antara realitas empiris dengan nilai-nilai
(teologis/tahuid) yang menjadi dasar konsepnya, dengan
usaha untuk mengubah realitas sesuai dengan nilai-nilai
teologis yang diyakininya itu. Realitas empiris yang
terjadi dalam penafsiran Hanafi adalah terjadinya
kolonialisasi oleh Barat dalam bentuk imperialisme
budaya.
Realitas tersebut menurut kesadaran Hanafi perlu
dilakukan perlawanan melalui jalur revolusi kebudayaan.
Teori oksidentalisme yang ditawarkan Hanafi adalah
salah satu upaya memperdalam agenda-agenda imperialisme
budaya dengan mempelajari masuk ke dalam sistem Barat.
Oksidentalisme adalah antitesis dari orientalisme yang
Barat telah mempelajari secara mendalam mengenai dunia
non-Barat. Namun, terkait oksidentalisme Hanafi dalam
kajian ini tidak akan dibahas secara mendalam karena
fokus kajian yang berbeda.
Realitas tersebut diatas kemudian disandingkan
dengan nilai-nilai keagamaan yang oleh Hanafi lebih
difokuskan pada sisi teologis atau tauhidnya. Hanafi
meyakini bahwa tauhid adalah mengandung dua sisi yakni
teologis dan humanisme sebagaimana telah diterangkan
dimuka. Sisi teologis ini dijadikan pijakan nilai
apabila realitas yang terjadi tidak sesuai, maka
dilakukan tindakan (action) terhadap realitas sehingga
pada akhirnya realitas dan nilai berada pada titik
sejajar.
Untuk menyelaraskan antara realitas dengan nilai,
adalah persoalan paling pelik. Karena menggiring
realitas untuk mencapai tatanan nilai tertentu
membutuhkan waktu sangat panjang. Heterogenitas
masyarakat, ideologi, nalar, budaya dan varian
masyarakat yang banyak akan cukup sulit diarahkan
menuju tatanan yang sama. Belum lagi, tatanan yang
diharapkan Hanafi merupakan tatanan yang menentang arus
besar peradaban (Barat). Yang dimana mayoritas
masyarakat dunia mengkiblatkan peradabannya pada Barat.
Barat sentrisme di wajah Hanafi merupakan fokus
perhatian dalam pergerakan Kiri Islam. Ia menilai bahwa
salah satu tugas Kiri Islam adalah untuk mengembalikan
Barat pada batas-batas ilmiahnya dan mengakhiri mitos
mendunianya. Penilaian Hanafi terhadap Barat khususnya
dalam aksi kolonialisme, imprealisme, kapitalisme,
barbarian, dispose, matrealistik dan segala bentuk
kecacatan sosial kultural yang ia sandarkan kepada
perspektif historis sehingga secara sengaja ia membuka
wajah peradaban Barat. Pembukaan wajah peradaban Barat
ini seharusnya menjadi sebuah perbandingan studi
bagaimana dunia Islam belajar mengembangkan
peradabannya minimal selangkah lebih maju dari Barat
dengan menafikan wajah buruk peradaban Barat. Sehingga
wacana ini bukanlah sekedar wacana dalam tugas Kiri
Islam akan tetapi implementasinya secara kongkret dalam
dunia Islam.
Hanafi mengkritik kemunduran peradaban Islam
disebabkan terlalu mendominasinya sandaran teologis
para penganut agama dan mengabaikan faktor humanisme
keagamaan. Hanafi menganalisis, tingginya perkembangan
sufisme, yang memberatkan pada aspek ukhrawi dan lebih
condong meninggalkan aspek duniawi menjadi awal
kemunduran Islam. Selanjutnya didukung dengan
pergeseran rasionalisme masyarakat menuju tatanan
sufisme secara besar-besaran. Terjadi eksodus gelombang
rasionalis menuju sufisme. Dalam hal ini, Hanafi
menunjuk Imam Al Ghazali sebagai pelaku utama gelombang
eksodus.
Hanafi memandang bahwa perkembangan sufisme dengan
cara pandang yang mendominasikan teologis dan
mengalienasikan humanisme menyebabkan kemunduran nyata
Islam dalam sejarah dunia. Islam tidak lagi menjadi
pemimpin peradaban dengan kekayanan sains, teknologi
dan rasionalisme namun justru mendewakan tahayul dan
mistisisme. Kemunduran terasa nyata setelah para
pemikir-pemikir Islam diarahkan menuju tatanan
keagamaan yang kaffah (sempurna) dalam lingkup
teologis.
Khazanah Islam klasik yang dimaksudkan oleh Hanafi
adalah bagaimana khazanah Islam klasik memasukan unsur
kemanusiaan dalam konteks ketuhanan. Artinya harus ada
korelasi antara konteks Ketuhanan dan kemanusiaan.
Menurut dia harus ada transformasi kebudayaan dari
pengetahuan tentang Tuhan pada pengetahuan tentang
manusia. Korelasi tersebut sebenarnya merupakan sebuah
wacana bagus dalam merasioanalisasikan khazanah Islam,
sehingga keislaman bukan saja sebagai dokrinisasi
terhadap praktik–praktik ritual keagamaan tetapi bisa
ditransformasikan kepada nilai–nilai kemanusiaan yang
universal.
Ditengah kemunduran Islam yang semacam itu, Hanafi
melihat Barat justru berbanding terbalik. Ia menjadi
pemimpin peradaban dengan menciptakan sistem yang lebih
rasional dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang pada beberapa abad terakhir menjadi kiblat
masyarakat dunia. Kemajuan Barat kemudian menciptakan
sistem kolonialisme dan imperialisme yang dipraktikkan
dalam bentuk militeristik dan budaya.
Imperialisme militeristik telah mulai luntur sejak
Perang Dunia Kedua, namun tahapan itu berganti pada
imperialisme budaya. Budaya Barat mencoba menguasai
segala aspek kemanusiaan masyarakat dunia. Dan lambat
laun, masyarakat dunia akan menjadikan Barat sebagai
negara yang memiliki peradaban tinggi serta mengabaikan
budaya asli masyarakat masing-masing negaranya itu.
Tidak hanya dalam batasan negara, imperialisme budaya
ini juga menyerang budaya dan tradisi keagamaan,
termasuk diantaranya Islam.
Keadaan yang demikian itu menurut Hanafi adalah
keadaan yang harus diperangi. Islam harus mengambil
bagian untuk kemerdekaan umat manusia dari imperialisme
budaya tersebut. Sebab, imperialisme akan menjatuhkan
masyarakat dunia dan menggiringnya menjadi masyarakat
yang melupakan identitas kulturalnya. Sebuah sistem
untuk memperkuat dominasi Barat atas dunia.
Al Yassar Al Islam menawarkan solusi. Ia menjadi
alat revolusioner yang akan membebaskan masyarakat
dunia dari kehilangan identitas kulturalnya tersebut.
Selanjutnya, Al Yassar Al Islam akan menjamin
kemerdekaan tersebut untuk perdamaian umat manusia.
Hanafi memperkenalkan proyek akbarnya, Turats dan
Tajdid7, yakni proyek yang menjadi solusi untuk
bagaimana menyikapi tradisi klasik yang dimiliki oleh
Islam dan bagaimana menyikapi perkembangan di Barat.
Turats dan Tajdid adalah judul umum proyek ini secara7 Hassan Hanafi, Al Turath wa al-Tajdid, Titian Ilahi Press, Yogyakarta,2001, hal. 258
keseluruhan karena tidak hanya menterapi metodologi-
metodologi dalam turats klasik, tetapi juga menterapi
turas itu sendiri sebagai problematika warisan,
pengaruh psikologis pada jamahir sikap kita terhadapnya
dan sarana-sarana pengembangan dan pembaharuannya.
Sebab, gerakan yang hakiki sekaran gini adalah gerakan
pemikiran dan peradaban yang urgenisinya tidak lebih
kecil dibandingkan gerakan ekonomi atau gerakan militer
kalau justru bukan assasnya.
Kekalahan kontemporer pada dasarnya adalah
kekalahan rasional disamping kekalahan militer. Bahaya
yang mengancam sekarang ini bukan sekedar kehilangan
tanah, tetapi juga pembunuhan nyawa untuk selamanya,
disamping kita terseret kedalam kritik atas otentisitas
dalam turats klasik kita dan kirtik kontemporer kita
yang diusahakan oleh turats klasik kita dengan
kebudayaan-kebudayaan kontemporernya.
Turats dan Tajdid adalah proyek otentisitas dan
modernitas yang sampai sekarang setelah kekalahan
berturut-turut, belum mampu kita wujudkan dan belum
kita sentuh kecuali klaim dan pengakuan saja.
DAFTAR PUSTAKA
Norman Daniel’s, 1960, Islam and the West: The Making of an
Image, Edinburgh: Edinburgh University Press.
Harlod Coward and Godon S. Smith (eds), 2004, Religion
and Peacebuilding, State University of New York.
Mehdi Nakosteen, 1954, History of Islamic Origins of Western
Education. A.D, 800-1350 with an Introduction to Medieval
Muslim Education, University of Coloardo Press,
Coloardo.
Asghar Ali Engineer, 2007, Islam and Its Relevance to Our
Age, LKiS Yogyakarta.
Hassan Hanafi, 1994, Religious Dialogue and Revolution, Anglo
Egyptian Bookshop, Kairo.
Hassan Hanafi, 1999, Muqaddimah fi 'Ilm al Istigrab,
Jakarta, Yayasan Paramadina.
Hassan Hanafi, 2001, Al Turath wa al-Tajdid, Titian Ilahi
Press, Yogyakarta.