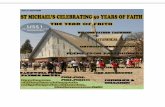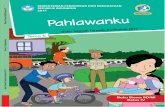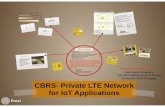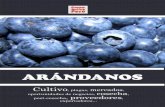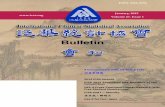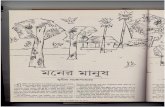Jurnal - WordPress.com
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Jurnal - WordPress.com
PENGANTAR REDAKSI
Jurnal Litbang Kesejahteraan Sosial merupakan media ekspose hasil-hasil penelitian bidangkesejahteraan sosial, yang terbit pada awal tahun 2006 ini menyajikan hasil penelitian tentangtenaga kerja wanita, pelacuran, pekerja anak, aksesibilitas non fisik bagi penyandang cacat, danperanserta masyarakat.
Pada era globalisasi ini, wanita yang bekerja di luar rumah bukan lagi hal yang tabu sepertipada masa Kartini dahulu. Tuntutan wanita untuk bekerja didasari keinginan mereka untukmembantu perekonomian keluarga, baik bekerja pada sektor formal (seperti direktris, manager,atau sekretaris) maupun sektor informal (seperti pembantu rumah tangga, buruh kasar maupunpekerja seks komersial). Indah Huruswati memotret permasalahan tenaga kerja wanita (TKW) keluar negeri secara ilegal di Kabupaten Sambas. TKW yang bekerja di luar negeri merupakandevisa bagi negara. Tetapi pada kenyatannya, banyak permasalahan yang dihadapi para TKWtersebut, hal ini terkait dengan rendahnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh mereka.Permasalahan TKW ini menjadi semakin kompleks karena tidak sedikit prosedur pemberangkatanmereka dilakukan secara ilegal yang pada akhirnya mereka hanya tersalurkan bekerja padasektor-sektor informal seperti pembantu rumah tangga (PRT) dan buruh kasar. Mukhlis dan BambangPudjianto menyajikan solidaritas antara para wanita penambang pasir di Desa Lumbung Rejo,Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman. Walaupun dihimpit masalah perekonomian, tetapi masihada ikatan yang kuat diantara sesama wanita penambang pasir. Mereka tidak segan untuk berbagiatau menolong jika ada penambang lain yang sedang kesulitan atau kesusahan walaupun merekasendiri serba kekurangan.
Tekanan ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah dan adanya iming-iming mendapatkanuang yang banyak dan mudah telah menjadikan tidak sedikit wanita mengambil “jalan pintas”dengan menjadi pekerja seks komerial atau pelacur. Berdasarkan hasil penelitian Irmayani diKabupaten Pati dan Jepara, pelacuran yang ada di daerah ini merupakan perilaku yang diturunkandan tidak terlepas dari sejarah masa lalu adanya pelacuran di daerah tersebut.
Krisis ekonomi yang berkepanjangan mengakibatkan tekanan ekonomi bagi keluarga. Halini tidak hanya berdampak pada wanita yang juga harus bekerja membantu perekonomiankeluarga, tetapi juga anak-anak dikerahkan untuk bekerja sehingga dapat membantuperekonomian keluarga. Yanuar Farida Wismayati memotret kondisi sosial pekerja anak di PesisirPantai Cumpat dan Nambangan, Bulak Banteng, Surabaya. Ada beberapa hal yangmempengaruhi anak bekerja yaitu tuntutan ekonomi keluarga dan faktor lingkungan pergaulananak.
Perhatian pemerintah terhadap penyandang cacat dalam aksesibiltas fisik sudah cukup baik.Tetapi dalam aksesiblitas non fisik masih kurang. Menurut penelitian yang dilakukan HaryatiRoebyantho, akseibilitas non fisik bagi penyandang cacat di Indonesia belum terperhatikan denganbaik oleh pemerintah. Dari 6 (enam) provinsi penelitian menunjukkan bahwa para penyandangcacat dan keluarganya mengalami kendala untuk memperoleh pelayanan informasi, pelayanankhusus dalam bidang sarana dan prasarana transportasi maupun pelayanan dalam mengikutipendidikan dan ketenagakerjaan.
Dalam melakukan pembangunan di perdesaan, perlu adanya peran serta aktif darimasyarakat maupun organisasi lokal agar tujuan dari pembangunan tersebut dapat tercapai.Suyanto menyajikan tulisan tentang pentingnya peran aktif dari kelompok/organisasi lokal yang
i
ada di mayarakat untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul,Yogyakarta. Wahana Kesejahteraan Sosial Masyarakat (WKSBM) yang merupakan jejaring kerjakelembagaan sosial komunitas lokal diharapkan dapat mengakomodir dan memobilisasimasyarakat dalam melakukan pembangunan kesejahteraan sosial. Ivo Noviana melihat pentingnyaperanserta masyarakat Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Bandung untuk menggali potensiyang ada di masyarakat. Dalam hal ini keberadaan lembaga sosial memegang peranan yangsangat penting. Tetapi pada kenyataannya, lembaga sosial yang ada tidak berjalan sebagaimanamestinya.
REDAKSI
i i
PERMASALAHAN PEKERJA MIGRAN DI DAERAH
PERBATASAN: STUDI KASUS TENAGA KERJA WANITA
DI KABUPATEN SAMBAS, KALIMANTAN BARAT
Indah Huruswati
ABSTRAK
Kasus TKW Indonesia yang mencuat baru-baru ini telah membuat keprihatinan pada berbagai pihak.Nasib mereka yang kurang beruntung disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilanyang dimiliki hingga akhirnya mereka hanya tersalurkan bekerja pada sektor-sektor informal seperti menjadiPRT, dan buruh kasar. Di daerah perbatasan Kalimantan Barat, permasalahan tenaga kerja menjadi semakinkompleks.
Memang para tenaga kerja ini mengalirkan nilai balikan ekonomi ke pedesaan, serta membawaperubahan sosial bagi keluarga yang ditinggalkan, terutama bagi tenaga kerja yang sukses dalampekerjaannya. Namun bagi tenaga kerja lainnya, yang tidak beruntung, tampaknya gambaran tentangkemulusan bekerja di luar negeri tidak sesuai dengan harapan dan iming-iming yang dijanjikan oleh agen-agen tenaga kerja.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, wawancara mendalam, danpengamatan. Dari kajian kasus ini, tampaknya masalah yang dialami TKW di Kabupaten Sambas lebihbanyak disebabkan karena prosedur pemberangkatan secara ilegal. Kebijakan pemerintah mendorong paracalo tenaga kerja menempatkan TKW ke Sarawak tanpa disertai dengan persyaratan dan perlindunganyang memadai.
I . PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Propinsi Kalimantan Barat denganpenduduk sekitar 4,03 juta jiwa, terdiri dari 2,06juta jiwa laki-laki dan 1,98 juta jiwa perempuan.Kurang lebih 26 persen di antaranya beradadi bawah garis kemiskinan dan sebagian besartinggal di pedesaan (BPS, 2004). Bila dilihatdari jumlah angkatan kerja penduduk di daerahKalimantan Barat ini, berdasarkan hasil Susenas2004 terlihat dari penduduk usia produktif, yangberjumlah 1.943.534, sebanyak 1.790.070 diantaranya yang bekerja. Kebanyakan darimereka bekerja di sektor informal seperti sektorpertanian. Sementara mereka yang tidaktertampung di sektor-sektor industri danpertanian di wilayah lokal, berusaha mencaripekerjaan di tempat lain bahkan menyeberangke wilayah Malaysia.
Rupanya, terbukanya peluang kerja diSarawak, Malaysia telah menjadi daya tariktersendiri bagi tenaga produktif yang tidakterserap pada usaha industri, baik di kota-kota
sekitar Kalimantan Barat maupun kota-kotalainnya di Indonesia. Hal ini terlihat sejak tahun1995, jumlah tenaga kerja Indonesia ke luarnegeri yang melalui propinsi Kalimantan Baratada sejumlah 46.922 tenaga kerja, terdiri dari20.044 tenaga kerja laki-laki dan 23.683tenaga kerja wanita (BP2TKI Pontianak, 2005).
Memang pengiriman TKI ke luar negerihingga saat ini telah menjadi salah satu alternatifyang cukup efektif untuk mengatasi masalahsemakin terbatasnya lapangan kerja di tanahair. Di samping mengalirkan nilai balikanekonomi ke pedesaan, juga membawaperubahan sosial bagi keluarga yangditinggalkan secara positif, terutama pola gayahidup keluarga mereka. Ini terutama bagitenaga kerja yang sukses dalam pekerjaannya.Sementara bagi tenaga kerja lainnya, yangtidak beruntung, tampaknya gambaran tentangkemulusan bekerja di luar negeri tidak sesuaidengan harapan dan iming-iming yangdijanjikan oleh agen-agen tenaga kerja. Bagimereka yang dikirim melalui Pengerah JasaTenaga Kerja Indonesia (PJTKI) secara resmi,tidak banyak menimbulkan masalah. Tetapi
1
tidak sedikit mereka yang pergi melalui agen-agen tidak resmi, banyak menimbulkanpermasalahan, terutama terjadi pada tenagakerja wanita (TKW).
Beberapa kasus yang terjadi pada tenagakerja wanita Indonesia belakangan ini cukupmemprihatinkan. Apalagi di daerah perbatasanKalimantan Barat, permasalahan tenaga kerjamenjadi semakin kompleks. Dari berbagaikasus yang ada, mereka yang menjadi buruhmigran dan korban perdagangan manusia inikebanyakan berasal dari Kabupaten Pontianak,Sambas, Landak, Sanggau, Sintang, Ketapang,dan Kota Pontianak.
Meskipun perhatian pemerintah kepadaTenaga Kerja Wanita di luar negeri sudah cukupbanyak, namun permasalahan yang muncultidak pernah selesai. Banyak kasus yangmenimpa TKW luput dari pantauan.Tampaknya penanganan masalah hanyabersifat “reaksioner”, menyelesaikan perkaraorang per orang, kasus per kasus. Baru ketikaTKW bermasalah, banyak pihak yangmeributkan. Sebenarnya masalah yangmenimpa TKW tidak pernah berhenti, setiapsaat ada yang namanya tindak kekerasan,penipuan, penganiayaan, dan pemerasan.Hanya apakah hal tersebut muncul di mediaatau tidak.
Memahami sosok TKW sebenarnya tidakhanya sekadar “perempuan yang bekerja diluar negeri, penghasil devisa negara danpahlawan keluarga”. TKW adalah sosokperempuan yang sudah jauh mengalamiperubahan dibandingkan dengan sebelummereka bermigrasi ke luar negeri. Mobilitasperempuan sebagai tenaga kerja yang tersebardi berbagai negara menyebabkan terbentuknyapengalaman baru, sehingga mereka cenderungmemiliki kepribadian lain dari sebelumnya.
B. Permasalahan
Permasalahan dalam penelitian ini adalahsejauhmana pihak-pihak terkait melakukanupaya penanganan masalah tenaga kerjawanita, yang hingga kini tidak pernah tuntasditangani. Pertanyaan penelitian menyangkut:
� Bagaimana permasalahan sosial tenagakerja wanita di daerah perbatasan?
� Bagaimana kebijakan dan programpelayanan kesejahteraan sosial TKW daritingkat propinsi hingga kabupaten?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalampenelitian ini adalah:
� Mengidentifikasi permasalahan tenagakerja wanita di daerah perbatasanKalimantan Barat.
� Mengetahui upaya-upaya pemerintah danpihak terkait dalam penanganan masalahketenagakerjaan.
� Mengetahui faktor-faktor penghambatpenyelesaian masalah tenaga kerjawanita.
D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan memberi-kan manfaat sebagai berikut :
� Menyajikan realitas positif maupun negatifdari kehidupan Tenaga Kerja Wanita(TKW), sehingga memberikan gambaranseimbang bagi calon TKW lain untukmengambil keputusan secara rasional.
� Memberikan masukkan kepada pengu-saha Pengerah Jasa Tenaga Kerja danbagi para penentu kebijakan, baik padatingkat Propinsi, Kabupaten/Kota maupuntingkat pusat, dalam merumuskan danmengimplementasikan kebijakan, untuktujuan meningkatkan kualitas kehidupanmasyarakat bukan sekedar keuntunganekonomi semata-mata.
E. Kerangka Pikir
Pertumbuhan ekonomi dan pengem-bangan pembangunan di semua sektor telahmenyebabkan meningkatnya permintaantenaga kerja. Hal ini tampaknya berlaku dinegara-negara seperti Malaysia, Singapura,Jepang, Arab Saudi dan sebagian negaraEropa. Peluang ini dimanfaatkan sepenuhnyaoleh tenaga kerja yang datang dari Indonesia.Jumlah mereka dari tahun ke tahun kianmeningkat, bahkan di antara mereka tidak lagimempedulikan syarat-syarat sah memasuki danbekerja di negeri orang.
2
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 1-14
Minat tenaga kerja Indonesia untuk bekerjadi luar negeri dipengaruhi oleh faktor-faktordalam negeri sendiri, seperti faktor pertumbuhanpenduduk yang tinggi, lapangan kerja yangsangat terbatas, sumber pendapatan yang tidakmemadai, dan faktor pengambilan tenaga kerjayang belum tersalurkan seluruhnya. Sedangkanfaktor dari luar negeri, selain untuk mencaripengalaman, motif utamanya adalah untukmendapatkan upah yang lebih baik sehinggadapat mensejahterakan keluarga di daerahasalnya. (Budiman, 2004: 379)
Mobilitas angkatan kerja ke luar negeridikenal dengan sebutan Tenaga Kerja Indone-sia (TKI). Ketika itu yang disebut TKI adalah laki-laki, tetapi kemudian muncul angkatan kerjawanita ke luar negeri, mereka disebut TenagaKerja Wanita (TKW). Tenaga kerja wanita yangdimaksud dalam penelitian ini adalah wanitayang bekerja sebagai tenaga kerja luar negeri.Umumnya mereka merupakan tenaga kerjatidak terampil (unskilled). Mereka hanyaberpendidikan sekolah menengah dan tidakmenguasai keterampilan khusus. Keadaan inimemberi pengaruh yang besar bagi kehidupansosial pekerja tersebut, sehingga kedudukanmereka sebagai ‘buruh’ sering dipandangrendah oleh majikan.
Departemen Tenaga Kerja (Depnaker)merupakan lembaga pemerintah yang berfungsisebagai penyalur informasi kesempatan kerjayang ada di dalam dan di luar negeri.Lembaga ini juga menyiapkan pelatihan-pelatihan bagi calon tenaga kerja yang akandisalurkan. Pelatihan-pelatihan semacam itu kinijuga telah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga penyalur tenaga kerja swasta yangbernaung di bawah Depnaker dan ataspengawasan Depnaker. Pada dasarnyalembaga-lembaga swasta ini membantu calontenaga kerja memperoleh pekerjaan denganmengambil sedikit keuntungan dari biayapendidikan yang dikeluarkan oleh calon tenagakerja. Ironisnya, kebanyakan lembagapelatihan, baik yang diselenggarakanpemerintah maupun swasta, cenderungmemberikan pelatihan domestik, misalnya untukkeperluan mengurus rumahtangga saja. Olehkarena itu, angkatan kerja wanita Indonesia tidakmengalami perubahan status. Mereka tetapmenjadi sub-ordinat dalam sebuah sistemkekuasaan (Abdullah, 1997).
Depnaker seringkali juga lambat me-nangani proses pengiriman tenaga kerjadibandingkan lembaga-lembaga swasta.Akibatnya, lembaga swasta mempunyai peranyang lebih besar, dampak lebih jauh adalahtenaga kerja menghadapi resiko yang lebihbesar juga. Namun sayangnya, orientasilembaga penyalur tenaga kerja swasta ini hanyapada pemenuhan target permintaan pasardaripada kualitas tenaga kerjanya, sehinggacalon-calon tenaga kerja yang dikirim hanyamemiliki keterampilan dan kemampuanterbatas.
Sering pula terjadi, kedatangan tenagakerja Indonesia di luar negeri, secara serempakberada di luar pengawasan pihak penguasa,yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak resmi.Tindakan seperti ini memberi keuntungan bagipihak agen dan majikan, sementara bagipekerja akan mengalami kerugian. Ironisnya,mereka terus datang meskipun tanpamempersiapkan dokumen-dokumen yang sah.Banyak tenaga kerja Indonesia yang masuk kenegara lain tanpa ijin. Dari keadaan seperti ini,lahirlah sindikat pendatang haram yangmembawa masuk pekerja tanpa ijin denganmembayar uang muka yang mahal. Para tenagakerja inipun menyanggupi untuk memberi uangmuka dalam jumlah besar kepada agen ataupengerah jasa tenaga kerja atau sering puladisebut ‘tekong’ liar dengan harapanmemperoleh pekerjaan.
Dalam keadaan mendesak, para pekerjatidak mempunyai pilihan lain kecuali mengikutikehendak majikannya. Ia terjebak dalamperangkap majikan yang hanya mempunyaidua pilihan, yaitu terus bekerja dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh majikan secarasepihak atau diserahkan kepada polisi karenatidak memiliki dokumen yang sah. Ancamanyang sangat merugikan ini sering dialami olehtenaga kerja wanita dan sebagian dari merekamenjadi obyek kekerasan majikan. Keadaanseperti ini sama halnya dengan sistemperdagangan ‘budak’.
Keputusan Menteri Tenaga Kerjamenyatakan bahwa setiap calon tenaga kerjaharus lulus administrasi, keterampilan dankesungguhan niat, dan seharusnya setiaptenaga kerja wajib mendapat perlindunganundang-undang (hukum). Ini bertujuan untukmemastikan seorang pekerja dapat men-
3
Permasalahan Pekerja Migran di Daerah Perbatasan (Indah Huruswati)
jalankan tanggung jawabnya dengan aman.Pihak majikan juga tidak akan memperlakukanpekerjanya di luar prosedur hukum yang berlaku,dengan alasan menganggapnya sebagai‘buruh semata’. Dengan demikian, pelak-sanaan undang-undang perburuhan secarasempurna bisa memberi keuntungan kepadapihak-pihak yang melakukan kontrak. Bagipihak majikan, hal itu akan berguna untukmempermudah pengawasan terhadap pekerja.Sedangkan bagi pihak buruh sendiri, akanbekerja dengan penuh keyakinan dankenyamanan. Dengan demikian akan terwujudrasa kemanusiaan, yaitu saling memerlukan dansaling menjaga, serta menghormati antara satudengan yang lain.
F. Metodologi Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalampenelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yangdimaksudkan untuk melihat, mendengar,sekaligus memahami gejala sosial dan budayayang berlaku pada masyarakat di lokasipenelitian. Penelitian ini dilakukan di perbatasanKalimantan Barat, yaitu di Kabupaten Sambas.Lokasi ini dipilih secara purposif berdasarkanpada daerah pemberangkatan/pemulangantenaga kerja wanita. Banyak permasalahanberkaitan dengan tenaga kerja wanita di daerahperbatasan, antara lain banyaknya calo/agentenaga kerja berkeliaran ke tempat tinggalpenduduk mencari tenaga kerja untuk dikirimke Malaysia sebagai tenaga kerja ilegal, selainitu juga tidak sterilnya area perbatasan sehinggamemungkinkan masyarakat sekitar dapat keluarmasuk wilayah perbatasan tanpa prosedur yangrumit.
Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data digunakanteknik pengumpulan data yaitu:
1. Studi kepustakaan. Mencari dan meng-analisa dokumen dan tulisan, berkaitandengan tema-tema yang berhubungandengan ketenagakerjaan dan kajiantentang perempuan, serta kebijakan yangterkait dengan pelayanan kesejahteraansosial.
2. Pengamatan lapangan (observasi). Peng-amatan dilakukan terhadap fenomena-fenomena sosial budaya yang terjadi
pada pelbagai kegiatan dan perilakuyang ada di lokasi penelitian.
3. Wawancara mendalam. Dalam wawan-cara ini yang menjadi informan utamaadalah tenaga kerja wanita, yang dipilihsecara purposif berdasarkan kriteriaberhasil dan gagal dalam pekerjaannya.Informan lainnya yang diambil adalahpetugas Dinas Sosial Propinsi Kalbar,Petugas Dinas Tenaga Kerja Transmigrasidan Sosial Kabupaten Sambas, Pember-dayaan Perempuan dan BP2TKI Kaliman-tan Barat dan LBH PIK Pontianak.
Untuk keperluan wawancara, digunakanrekaman wawancara. Teknik ini digunakandengan maksud agar memudahkan penelitimemahami keterangan-keterangan yangdiberikan. Wawancara tanpa struktur yangmerupakan bagian dari wawancara tanparencana, banyak digunakan dalam penelitianini. Semua teknik wawancara dilakukan secarabebas dan terfokus, maksudnya adalah agarinforman mendapat kebebasan untuk berceritadengan caranya sendiri, dalam kontekskebudayaannya.
I I . HASIL PENELITIAN
A. Kondisi Wilayah PerbatasanKabupaten Sambas
Panjang garis perbatasan Indonesia-Ma-laysia, sepanjang Kalimantan Barat ada 2400km, di antaranya ada sejumlah 966 patoksebagai batas wilayah Indonesia. Kondisinyatidak cukup layak, karena ada beberapa diantaranya mengalami kerusakan, bahkan adayang hilang. Secara alamiah terdapat sekitar50 jalur jalan setapak yang menghubungkan55 desa di Kalimantan Barat dengan 32kampung di Serawak. Sesuai dengankesepakatan Pemerintah Indonesia dan Malay-sia pada tahun 1967 dan 1984 terdapat 15pintu masuk (entry point) di wilayah Indonesiadan 8 pintu masuk di wilayah Malaysia. MenurutWakil Gubernur Kalimantan Barat, L.H. Kadir,“Saat ini sedang tahap pembicaraan akandisepakati mengenai penambahan 1 entry pointlagi sehingga menjadi 16 dan Malaysiaditambah 2 entry point sehingga menjadi 10.”(Pontianak Post, Sept. 2005).
4
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 1-14
Kabupaten Sambas terletak di bagianpaling utara propinsi Kalimantan Barat, sebelahselatan dan timur berbatasan denganKabupaten Bengkayang, sebelah barat denganLaut Natuna dan sebelah utara dengan Ma-laysia Timur (Sarawak). Jarak dari KabupatenSambas ke wilayah perbatasan Malaysia Timurdapat ditempuh melalui beberapa jalur daratdengan menggunakan Pos Lintas Batas (PLB)di Aruk (wilayah Indonesia) dan Biawak (wilayahMalaysia). Di Kabupaten Bengkayang terdapatjalur PLB yaitu di Jagoi Babang (Indonesia) danSerikin (Malaysia). Selain itu terdapat beberapajalur setapak (jalan tikus) yang biasa digunakanoleh mereka yang ingin bekerja di Malaysiasecara tidak resmi. Lama perjalanan kuranglebih 4 jam dengan menggunakan bis dariibukota Kabupaten Sambas ke wilayahperbatasan Malaysia Timur.
Ada satu jalur lagi yang biasa digunakanuntuk melakukan perjalanan ke daerahperbatasan yaitu desa Temajuk di KecamatanPaloh yang menghubungkan dengan desaMelanoh di Malaysia. Perjalanan yangditempuh menuju desa Melanoh, cukupberbahaya. Bisa menggunakan kendaraandarat maupun laut. Kalau melalui laut (melaluiperbatasan laut Natuna), perjalanan sepanjang40 km ditempuh selama 6 jam dengangelombang yang tinggi. Sedangkan bilamelalui darat, jalannya penuh lumpur danberbatu-batu, dapat ditempuh selama 5 jam.
Sekarang ini sedang disepakati konsepBorder Development Center (BDC), yaitu konseppengembangan pusat pertumbuhan diperbatasan yang dititikberatkan pada 5kawasan yang terdiri dari Entikong–Sanggau,Nanga Badau–Kapuas Hulu, Temajo dan Aruk,Jagoi Babang dan Jasa. “Pusat-pusat itudiharapkan akan menjadi prime moverpengembangan kawasan perbatasan secarakeseluruhan. Selain itu, kita mengembangkanpembangunan di daerah pantai sebagaipembangunan Kalimantan Barat bagiantengah,” kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat(Pontianak Post, 2005).
Tampaknya pembangunan wilayahperbatasan Kalimantan Barat belum mendapatperhatian yang mendalam, sehingga banyakpermasalahan sosial maupun ekonomi yangmemiliki nilai strategis yang dapat mendoronginstabilitas keamanan di sepanjang perbatasankedua negara.
B. Permasalahan TKW di DaerahPerbatasan
Kasus-kasus yang terjadi pada TKWbiasanya terkait dengan penipuan paracalo yang ingin mempekerjakan mereka.Kebanyakan yang terjadi, para korban tidakmengenal dengan pasti calo yang membawamereka. Itulah yang menjadi kelemahan TKWkita, yang tidak mengetahui dengan jelasidentitas orang-orang yang membawa mereka.Kalau sampai terjadi kasus yang seperti ini,biasanya dilacak ke majikan-majikan yangmempekerjakan para TKW ini. Yang agak sulitadalah ketika korban sudah berpindah caloatau majikan dari tangan ke tangan, misalnyadari Sambas si TKW dibawa oleh A, yangdiketahui oleh TKW hanya A saja. Tetapi ketikasampai di perbatasan Malaysia, si TKWdiserahkan lagi ke B, baru dibawa ke majikan,atau kadang ada yang masih berpindah tanganlagi. Sulit mencari identitas para calo.
Bila terjadi masalah dengan tenaga kerja,seringkali majikan tidak mendukung pe-nanganan masalahnya. Begitu juga bilamasalah yang muncul terkait dengan gaji yangtidak dibayar, ini lebih disebabkan karenamajikan beranggapan, mereka merasa sudahmembeli TKW tersebut dari tangan agen/calo.Tampaknya tidak ada kepedulian majikanterhadap kasus yang dihadapi TKW.
Pada umumnya masalah-masalah yangdialami TKW di Kabupaten Sambas lebihbanyak disebabkan karena prosedur pem-berangkatan secara ilegal. Masyarakat tidakmengetahui atau kurang informasi tentangmekanisme bekerja ke luar negeri secara legal.Seorang aktivis perempuan di Sambas yangpeduli terhadap masalah TKW di sekitar tempattinggalnya, mengatakan bahwa sebagian besarcalon TKW mempunyai anggapan jika sudahmemiliki paspor sudah dianggap legal/resmimenjadi TKW ke luar negeri. Padahal dalamkenyataan mereka berangkat hanya meng-gunakan visa pelancong, bukan visa kerja.Adapula yang hanya menggunakan surat dariPos Lintas Batas (PLB) sebagai ijin masuk keMalaysia. Bahkan ada yang sama sekali tanpadokumen apapun.
Berkaitan dengan banyaknya tenaga kerjayang bermasalah, menurut Sofwan Barnas,Kepala Sub Dinas Pelatihan dan PenempatanTenaga Kerja, Disnakertrans Pontianak, dalam
5
Permasalahan Pekerja Migran di Daerah Perbatasan (Indah Huruswati)
tiga tahun terakhir ada kecenderungan aruskedatangan TKI ilegal ke Sarawak terusmeningkat. Malah dalam perkembanganterakhir, tiap bulan bisa mendeportasi hingga500 orang TKI bermasalah ke wilayahKalimantan Barat. Sebagian besar dari merekayang dideportasi baru keluar dari penjaralantaran melanggar dokumen keimigrasian ataumelakukan tindak kriminal. Kondisi tersebutmenunjukkan intensitas lalu lintas WNI secarailegal di Sarawak relatif tinggi. “Diperkirakansaat ini tidak kurang dari 10.000 WNImendekam di sejumlah penjara, dan begitudilepas langsung dideportasi ke Kalbar setiaphari Senin dan Jumat sepanjang tahun,” ujarSofwan.
Apabila tiap tahun TKI ilegal masuk keSarawak berjumlah 100.000 orang, diper-kirakan periode yang sama keberadaan TKIbermasalah bisa mencapai lebih dari dua kalilipat. Mereka terdorong mengambil jalan pintas,karena tuntutan ekonomi dan ketidaktahuanmengenai aturan, sehingga mudah terjerumuske dalam cengkeraman para calo yang sudahmembentuk jaringan mafia. “Sangat sulitdiberantas. Jaringan mafianya sangat rapi.Jumlah rombongan yang dideportasi biasanyabisa mencapai ratusan orang. Mereka sangatpatuh terhadap sejumlah instruksi dari para calo,untuk selanjutnya kembali ke Sarawak denganidentitas lain di dalam paspor,” ujar Sofwan.Biasanya para TKW yang baru dideportasi,terbujuk kembali oleh para calo atau temansekerja di luar negeri untuk pindah perusahaandengan iming-iming upah yang lebih besar.
Semakin merajalelanya para calo ini,salah satunya juga disebabkan oleh kebi-jaksanaan JP Visa yang diterapkan olehPemerintah Sarawak sehingga mendorong paracalo menempatkan TKW ke Sarawak tanpadisertai dengan persyaratan dan perlindunganyang memadai.
Sofwan mengatakan, sebetulnya tiap tahunSarawak membutuhkan tenaga kerja asingsekitar 100.000 orang untuk dipekerjakan disektor perkebunan, perkayuan dan konstruksi.Dari jumlah itu, yang dikirim secara legal keSarawak tiap tahun melewati Kalimantan Barat,tidak sampai 10 persen. Menurutnya lagi, TKWformal dan informal yang kembali denganbermasalah itu sudah mengandung unsurtrafficking. Ini bisa terjadi karena para TKW ituditipu.
Umumnya kesulitan menangani kasus-kasus TKI ilegal adalah karena hampir semuatidak memiliki identitas lengkap. Kondisiini menyebabkan sangat sulit mintapertanggungjawaban pada perusahaanatau majikan yang mempekerjakan.“Pertanggungjawaban ini sangat pentingkarena mereka perlu ongkos pulang untukkembali ke kampung halamannya, upahbekerja, serta biaya pengobatan jika dirawatdi rumah sakit,” kata Sofwan.
Menurut laporan Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kalbar, sektor lapangan kerjayang diperkirakan mempunyai banyak tenagakerja bermasalah antara lain adalah pekerjaanrumah tangga (selama ini tidak ada permintaanresmi); pertokoan dan kedai makananminuman (permintaan sangat kecil); home in-dustry dan industri kecil (permintaan sangatkecil); dunia hiburan (tidak ada permintaanresmi); perkapalan/nelayan (tidak adapermintaan resmi); perkebunan kelapa sawitdan perkebunan kecil lainnya (penempatantidak sebanding perkiraan kebutuhan), dankonstruksi bangunan.
C. Dua Kasus TKW Di DaerahPerbatasan
Kasus TKW gagal: Marlina
Kasus ini ditangani oleh Yayasan LBH-PIKPontianak pada tahun 2003, yang terjadi padaseorang TKW berasal dari KecamatanSejangkung, Sambas. Dia mengalami patahkaki karena loncat dari jendela rumah majikanuntuk menghindari tindak perkosaanmajikannya itu.
Kisahnya berawal pada pertengahan1995, ketika itu Marlina dan 3 orang temannya,Leny, Azizah dan Rusnita bertemu Konedi, salahseorang agen tenaga kerja Indonesia yangkebetulan tinggal tak jauh dari kampungmereka di desa Sekuduk, Sejangkung Sambas,Kalimantan Barat. Mereka terlibat pembicaraanserius seputar peluang kerja di Malaysia.Menurut Konedi, jika ingin bekerja di negeri itu,ia bisa membantunya dengan mudah.“Kebetulan ada pekerjaan sebagai penjagatoko sayuran. Kerjanya ringan, kalian hanyamelayani pembeli saja”, kata Konedi kepadaMarlina ketika itu.
6
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 1-14
Konedi menceritakan kenikmatankehidupan di Malaysia kepada ke empat gadistersebut. Selain dijanjikan gaji yang cukupbesar, kesenangan lainpun pasti merekadapatkan dengan mudah. Dengan penghasilanyang diperoleh nanti, mereka bisa membelirumah, perhiasan, sawah dan sebagainya.Begitu iming-iming Konedi kepada Marlina danteman-temannya. Marlina dan teman-temannya tertarik dan menyatakan ke-inginannya untuk bisa bekerja di Malaysia.
Selain janji-janji muluk, Konedi jugamenjanjikan membantu biaya keberangkatan,pengurusan pasport, dan kelengkapan surat-surat lainnya. Ketika itu Marlina juga mendapatdukungan dari orangtuanya, bahkan merekaturut memberi bekal uang kepada Marlina.Sempat juga orangtua Marlina merasa khawatirdengan kepergiannya, tetapi karena Marlinapergi tidak sendirian dan Konedi juga sudahdikenal mereka, maka orangtua Marlinamelepaskan kepergiannya dengan pasrah.
Marlina dan ketiga temannya sepakatmenentukan hari keberangkatan sambilmenunggu surat-surat yang diperlukan yangkatanya, sedang diurus oleh Konedi. Namunternyata, sampai batas waktu yang sudahditentukan, Konedi tidak melakukan usahaapapun dalam mengurus dokumen yangdiperlukan. Akhirnya mereka berangkat keMalaysia tanpa dilengkapi dokumen resmi.Mereka masuk melalui Serikin, daerahperbatasan Kalimantan Barat (Indonesia)dengan wilayah Kuching (Malaysia).
Tanpa Dokumen Resmi
Setibanya di perbatasan, Konedi mem-perkenalkan ke empat gadis itu kepada seorangwarga negara Malaysia, yang ternyata jugaagen tenaga kerja ilegal. Ke empat gadis itulangsung dibawa ke suatu tempat di kotaKuching. Di sana mereka ditempatkan dalamsatu rumah selama hampir 1 bulan.
Rencana semula mereka akan dipe-kerjakan pada satu tempat yang sama, tetapiternyata mereka ditempatkan terpisah. Satupersatu mereka diberangkatkan. Marlinadiberangkatkan lebih dulu, baru kemudianteman-teman lainnya. Marlina dibawa padaseorang Tionghoa, yang akan menjadimajikannya. Janji sebagai pelayan toko ternyata
tidak sesuai. Marlina dipekerjakan sebagaipembantu rumah tangga. Terpaksa pekerjaanitu ia jalankan juga.
Selama enam bulan bekerja, Marlina tidakpernah mendapat gaji. Bahkan memasuki bulanke delapan, Marlina diserahkan kembalikepada agen tanpa menerima uang sepeserpun. Selanjutnya, Marlina diserahkan lagikepada seorang janda kaya bernama Helenyang tinggal di Kuching.
Makan Sekali Sehari
Ternyata ikut dengan majikan baru puntidaklah beda dengan yang lalu. Keinginanuntuk mendapat majikan yang lebih baik, takpernah kesampaian. Setiap hari Marlina bangunjam 5 pagi, tanpa istirahat merampungkanberbagai pekerjaan hingga pukul 21.00.Pekerjaan yang dilakukan mulai dari menyapu,mencuci, memotong rumput sampai memberimakan anjing, semua dilakukannya sendiri.Juga pekerjaan lain seperti membersihkansaluran air dan sebagainya. Untuk mengerjakanitu semua, ia hanya diberi makan sekali dalamsatu hari.
Jika ada pekerjaan yang kurang berkenanuntuk majikannya, tak segan-segan ia dimarahidan dipukul. Pemukulan terkadang tidak hanyamenggunakan tangan, tetapi juga meng-gunakan gagang sapu yang terbuat daribambu atau rotan.
Selama lima tahun bekerja dengan Helen,Marlina terus mendapat perlakuan yang tidaksenonoh dan selama itu pula ia tidak pernahmenerima gaji yang menjadi haknya. Hal iniberarti, selama itu pula ia tak pernah mengirimuang kepada keluarga yang ditinggalkannya.Jangankan untuk mengirim uang, mengirimkabar pun ia tidak diperkenankan majikan.Selama tinggal di rumah itu, ia merasa sepertidikurung karena dilarang keluar. Bila ketahuania keluar rumah, tak pelak lagi pukulan akanmendarat di tubuhnya. Ia pernah berusahakabur dari rumah itu, tetapi gagal.
Disiksa Sampai Lumpuh
Tindak kekerasan terparah yang dilakukanHelen kepada Marlina adalah pemukulanyang diarahkan ke bagian belakang leher danbagian tulang belakang Marlina. Pukulan
7
Permasalahan Pekerja Migran di Daerah Perbatasan (Indah Huruswati)
dilakukan berulang-ulang hingga menye-babkan terganggunya saraf otak sehinggaMarlina mengalami kelumpuhan. Melihatkondisi Marlina seperti itu, Helen membawaMarlina ke rumah sakit. Ada rasa takut rupanyadalam diri Helen. Ketika itu dokter mengatakan,Marlina perlu mendapat therapi dan perawatanyang cukup intensif.
Helen tidak punya keinginan untukmerawat Marlina yang kondisinya tampakparah itu. Akhirnya melalui seorang kenalanHelen, seorang warga Pontianak, ia menitipkanMarlina untuk dikembalikan kepada keluarga-nya di desa Sekuduk, Kalimantan Barat. Marlinaakhirnya dapat kembali ke keluarganya,dengan dibekali uang ala kadarnya dansejumlah pakaian yang masih cukup layakpakai.
Melihat kondisi Marlina, keluarganyasangat terkejut. Berbagai upaya dilakukan untukkesembuhan Marlina, dari pengobatan medishingga pengobatan alternatif. Tetapi semuanyatidak membawa hasil.
Atas saran berbagai pihak, kemudianayah Marlina mencoba menghubungi YayasanLembaga Bantuan Hukum (YLBH) PIK diPontianak untuk menyelesaikan masalah inimelalui jalur hukum. Lewat kuasa hukum yangdipimpin Hairiah, SH akhirnya masalah Marlinadiupayakan penyelesaiannya. (informasidiperoleh dari Yayasan LBH- PIK Pontianak)
Kasus TKW berhasil: Farida
Farida bekerja sebagai tenaga kerja In-donesia karena melihat banyak tetanggaberhasil dalam kehidupannya setelah merekakembali sebagai tenaga kerja luar negeri.Farida berniat untuk menjadi tenaga kerja diMalaysia daripada di rumah tidak adapekerjaan. Ia sempat menamatkan SMEA tahun1987 dan mencoba melamar pekerjaan dibeberapa perusahaan, tetapi tidak pernahmembuahkan hasil. Hingga saat ini ia belumberkeluarga dan pernah bekerja di Malaysiaselama 2 tahun (tahun 2002–2004). Ketikakembali dari Malaysia, penghasilan yangdiperoleh dijadikan modal untuk membukausaha warung. Kini dia dapat hidup dari usahawarungnya dan dapat menanggung hiduporangtuanya.
Prosedur Pemberangkatan
Ketika tahun 2002 Farida diajak olehtetangga ke PJTKI untuk mendaftarkan dirisebagai tenaga kerja di Malaysia. Ia melihattetangganya itu telah berhasil sebagai tenagakerja dan ini menjadi motivasi bagi dirinya untukikut bersamanya. Ketika itu orangtuanyamelarang bila ia pergi seorang diri. AkhirnyaFarida ikut mendaftar bersama bang Udin(tetangganya). Barulah ia diberi ijin orangtua.Apalagi ada satu persyaratan dari PJTKI yangharus dipenuhi jika ingin bekerja di Malaysia,yaitu harus ada ijin dari orangtua. Bagi merekayang sudah berkeluarga harus ada ijin darisuami, kemudian juga harus ada ijin dariKepala Desa dan pengurusan kartu keluarga,KTP serta surat-surat atau dokumen lainnya yangdibutuhkan.
Semua persyaratan yang dibutuhkanseperti KTP, pasfoto, Kartu Keluarga, AkteKelahiran dan Ijazah, diurus oleh PJTKI. Faridahanya tinggal berangkat saja. Karena tempattinggal Farida dekat dengan kantor PJTKI,maka ia tidak perlu ditampung di tempat itu.Lamanya proses dari masuknya berkas-berkas/dokumen ke PJTKI paling lama sekitar 3 bulananatau cepat lambatnya tergantung daripermintaan Malaysia. Masa tunggu inibiasanya berlangsung paling lama 6 bulan danuntuk keperluan keberangkatan ini, ia tidakditarik biaya apapun. Semua biaya ditanggungoleh perusahaan dimana nantinya ia bekerja.
Untuk dapat bekerja di Malaysia tidakada proses seleksi/ditest, Farida hanyamendaftarkan diri di PJTKI dan dinyatakan pastiberangkat. Namun sebelumnya, harus medicalcheck up dulu untuk mengetahui penyakit yangdiderita setiap calon tenaga kerja (sepertimenderita penyakit typus). Untuk keperluan inidibutuhkan biaya sebesar Rp. 70.000,-. Selamamasa tunggu keberangkatan, Farida ikuttemannya berjualan.
Ketika berangkat ada sekitar 200 orangbersama-sama pergi dengan dirinya. Merekasemua bekerja di Malaysia pada perusahaan/pabrik yang sama, hanya ada 2 orang yangbekerja pada lain pabrik. Tenaga kerja yangberangkat ketika itu tidak hanya perempuantapi juga ada laki-laki. Mereka bekerja denganmenggunakan sistem kontrak selama 2 tahun,dan pada saat akan berangkat, mereka harus
8
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 1-14
menandatangani surat perjanjian kontrak sambildiberikan pengarahan dari pengurus PJTKItentang suasana lingkungan kerja di sana sertaperaturan yang harus mereka ikuti selamabekerja.
Beberapa tahun yang lalu, Farida pernahmenjadi TKW dan ketika itu dia berangkat padamalam hari sekitar jam 20.00 – 21.00 WIB.Tetapi sekarang, ketika pergi untuk kedua-kalinya, ia berangkat pada siang hari sekitarjam 13.00 WIB. Sebelum pemberangkatanjuga ada pertemuan dan wawancara.
Mereka berangkat dengan menggunakanbis dari Sambas menuju Entikong. Sesampainyadi perbatasan Entikong, hari sudah menjelangsubuh, mereka dijemput oleh bis Malaysia. Disana mereka diperiksa paspor, dan menunggusampai jam kerja Kantor Migrasi dibuka.Selama menunggu, mereka diberi makanandan minuman (snack dan sarapan).
Ketika Kantor Migrasi dibuka, paspordibagikan kepada pemiliknya masing-masinguntuk diperiksa dan diberi stempel. Kemudiandiserahkan lagi ke pengurus PJTKI dan distempeloleh PJTKI. Setelah paspor distempel laludiserahkan kepada supir bis yang ditumpangiagar bila ada pemeriksaan Polisi Malaysiadi perjalanan, tidak merepotkan. Polisi mem-berikan surat keterangan (pemberitahuan)kepada para TKI karena mereka tidakmemegang paspor sampai ke tempat tujuan(perusahaan). Surat keterangan tersebutlangsung diserahkan ke security.
Farida waktu itu bekerja di Samling MiriBaramas, yang terletak di Miri hampir diperbatasan Brunei Darussalam. Perjalananmenuju Miri memakan waktu selama 2 hari, danmereka tiba di Miri ketika subuh. Tiba di SamlingMiri Baramas, mereka dikumpulkan oleh secu-rity untuk pemeriksaan paspor satu per satu.Setelah itu, barulah mereka diantar ke asramadengan bis. Pengurus dari PJTKI hanyamengantar mereka sampai pengurusan pasporselesai.
Awal Bekerja
Di dalam perjalanan menuju Malaysia ini,ada rasa takut karena terpengaruh oleh suasanakerja yang baru, tetapi karena teman-temanseperjalanan banyak memberi masukantentang pekerjaan di perusahaan tersebut, rasa
takut itu dapat sedikit dikendalikan. Ditambahlagi PJTKI yang mengurus segala keperluannyasudah dipercaya dan tidak pernah terdengarbahwa PJTKI tersebut membawa lari gaji paratenaga kerjanya, serta telah terbukti banyaktenaga kerja yang dikirim tersebut, berhasildalam pekerjaannya.
Di sana mereka tinggal di kompleksperumahan dan satu rumah diisi oleh 6 orang.Makan juga ditanggung oleh perusahaan danketika jam makan, mereka berkumpul di kantin.Untuk keperluan sehari-hari seperti sabunmandi, sabun cuci, pasta gigi, dan lain-lain,mereka bawa sendiri dari Indonesia. Begitu jugadengan perlengkapan untuk bekerja sepertisepatu, celana panjang, dan lain-lain, sebelumkeberangkatan sudah diberitahu oleh PJTKIuntuk dibawa.
Sebelum bekerja, para tenaga kerjadiberikan brosur untuk memenuhi kelengkapansemua persyaratan bekerja dan selama tinggaldi Malaysia. Setelah itu Farida diberikan train-ing bekerja sebagai pembantu operator mesin,kalau tidak mampu melakukan pekerjaantersebut, dia bisa minta pindah ke bagian laindengan jangka waktu kerja yang sama.
Pengalaman Bekerja
Dalam bekerja mereka terbagi menurutshift A (sebanyak 3 orang) dan shift B (sebanyak3 orang) dan jam kerjanya siang-malam (24jam). Menurut perhitungan gaji perbulan, Faridamendapat gaji pokok sebesar 8 ringgit (± Rp.700.000,- s/d Rp. 800.000,-) ditambahdengan gaji overtime (lembur).
Penyesuaian diri dengan lingkungan disana, tidak begitu susah karena kebanyakandari tenaga kerja yang ada adalah orang In-donesia (seperti Jawa, Madura). Bahasa yangdigunakan sehari-haripun adalah bahasamelayu. Ada peraturan-peraturan yang harusdiikuti, di antaranya masuk kerja pada pukul07.00 (waktu setempat), pulang pukul 19.00waktu istirahat dua kali, lamanya kuranglebih setengah jam, yaitu pukul 12.00 dan pukul 16.00. Lalu pukul 18.00 – 19.00 barudibolehkan pulang. Pada saat ini adapergantian shift, dari shift A kepada shift B.Pekerjaan dilakukan sepanjang hari selama satuminggu penuh dan hari minggu adalah hariservice, maksudnya pada hari ini ada pergantianyang ketika dalam minggu kemarin kelompok
9
Permasalahan Pekerja Migran di Daerah Perbatasan (Indah Huruswati)
shift A bekerja pada pagi hari, maka mulaiminggu berikut mereka bekerja pada malamhari dan begitu juga sebaliknya dengankelompok shift B.
Bulan pertama bekerja, Farida diberi gajiseparuh dari gaji yang seharusnya diterima,karena ketika itu ia baru masuk bekerja padapertengahan bulan (tidak dipotong biaya-biayaapapun). Menurut peraturan perusahaantersebut, kalau tidak masuk bekerja dikenakanpotongan gaji, semua sudah ada per-hitungannya selama sebulan. Ada potongandari perusahaan untuk pembuatan pasporsebesar 50 ringgit tiap bulan selama 10 bulan.Setelah masa kontrak 2 tahun selesai, uangpotongan tersebut dikembalikan lagi, tapi kalauputus kontrak sebelum dua tahun, misalnyahanya satu tahun bekerja, uang tidakdikembalikan. Perusahaan juga menanggungmasalah kesehatan setiap tenaga kerja, sepertibila terjadi kecelakaan, langsung dibawa keklinik tetapi sebelumnya harus lapor dulu kesecurity.
Tenaga kerja di sana kebanyakan adalahtenaga kerja perempuan, menurut Farida kalautenaga kerjanya laki-laki, banyak yangmelarikan diri (kabur/tidak betah) dan jugaharus membuat paspor sendiri (mereka harusmenanggung biaya pembuatan paspor sendiri).Di tempat kerjapun mereka kadang-kadangjuga suka berkelahi.
Selama para tenaga kerja ini tinggal didalam kompleks perumahan perusahaan, adaperaturan yang harus ditaati, seperti pada waktumalam hari tidak boleh keluar kompleks,apabila keluar, ada batas waktu hingga pukul10.00 malam (waktu setempat), untuk asramaperempuan dibatasi dengan pagar. Apabilalewat dari jam 10.00 malam, pagarnya akandikunci dan security akan memeriksa semuakamar-kamar lelaki, apabila ada yangmelanggar dan tertangkap, dikenakan denda50 ringgit untuk satu orang. Pada siang hari,mereka diperbolehkan untuk keluar (adakebebasan) tapi harus minta ijin lebih dahulupada security, dan meminta surat ijin dariperusahaan untuk keluar kompleks perumahan.Hal ini harus mereka patuhi karena ketika keluar,mereka tidak membawa paspor. Kalau terjadisesuatu di perjalanan, mereka dapatmenunjukkan surat keterangan dari perusahaanatau kartu identitas kerja kepada polisi, jadi tidakperlu lagi membawa paspor kemana-mana.
Selama bekerja di perusahaan itu, per-gaulan dengan sesama pekerja juga dipantauoleh perusahaan. Misalnya bila ada pekerjayang hamil dengan sesama temannya,perusahaan akan memulangkan (dikeluarkan)kedua-duanya kembali ke Indonesia. Merekadikenakan sanksi berupa denda satu bulansebesar 80 ringgit yang harus dibayarkanselama sisa masa kerja di perusahaan tersebut.Mereka tidak boleh bekerja lagi di perusahaanitu (dikeluarkan dari pabrik), tetapi selama masatunggu kepulangan, mereka masih tetapmendapatkan makan. Biasanya prosesmenunggu kepulangan satu minggu lamanya.
Habisnya Masa Kontrak Kerja
Selama bekerja di perusahaan tersebut,paspor dipegang oleh perusahaan, tetapi kalaumasa kontrak kerja sudah habis, dan inginkembali ke Indonesia, paspor akan di-kembalikan lagi setelah sampai di Entikong dandistempel lagi untuk terakhir kali.
Apabila masa kontrak kerja sudah habis,pihak perusahaan memberitahu 3 bulansebelumnya kepada tenaga kerja yangbersangkutan. Kalau nama tenaga kerja yangsudah habis masa kontraknya, tidak ada didaftar kepulangan, bisa melapor ke kantor untukmengajukan permohonan pulang langsungatau ingin melanjutkan bekerja. Apabilamemilih untuk pulang, nama tenaga kerjatersebut dicantumkan dalam daftar, tetapi bilaingin melanjutkan pekerjaan, nama yangbersangkutan dikeluarkan dari daftar. Semuaini harus mereka urus jauh-jauh hari sebelumnyake kantor. Untuk kembali ke Indonesia, semuabiaya transportasi ditanggung oleh perusahaandimana mereka bekerja dan biasanya sudahdisediakan bis untuk kepulangan mereka.Kemudian diserahterimakan kepada pihak PJTKIyang mengirim di pintu perbatasan.
Bagi mereka yang masa kontrak kerjanyalebih dari 2 tahun, boleh mengambil cuti selama1 bulan tetapi ini dapat dilakukan setelah 2tahun bekerja. Perusahaan juga memberikancuti istirahat bagi mereka yang sakit. Istirahatdiberikan selama 1 hari dan dapat berobat keklinik perusahaan.
Pemanfaatan Penghasilan
Apabila sudah bekerja selama 1 tahun,pihak perusahaan menganjurkan kepada para
10
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 1-14
tenaga kerjanya untuk membuka rekening bank,gunanya untuk memudahkan mereka mem-berikan gaji kepada karyawannya (merekatidak perlu antri menunggu panggilan) selainitu dapat ditabung. Biasanya setiap dua bulansekali Farida mengirim uang dari hasil kerjanyakepada keluarga di kampung.
Selama 2 tahun bekerja di Malaysia,Farida dapat membawa uang sekitar Rp.6.000.000,- belum lagi kalau dia mengirim kekeluarga (paling sedikit ia mengirim Rp.400.000,- tiap 2 bulan sekali) dan denganpenghasilannya itu Farida dapat membukausaha warung sembako di samping rumahnya.Terakhir ketika mau pulang pada bulan ke-10,Farida sempat mengirim 1000 ringgit dari hasilarisan. Untuk penukaran uang ringgit ke rupiahmereka biasanya menukarkannya di toko emas,karena lebih besar (mahal) penukarannyadaripada di bank.
Kesan Terhadap PJTKI
Selama bekerja menjadi TKW melaluiPJTKI, Farida tidak pernah menemui masalah.Pelayanan yang diberikan oleh PJTKI tersebutsudah dianggap cukup baik dan juga tidak adamasalah dengan urusan imigrasi. PJTKI itu telahmengurus semua dokumen-dokumen yangdiperlukan. Menurut Farida, kalau ingin bekerjamelalui PJTKI harus mendaftar langsung sendiri(menulis nama dan menunjukkan KTP). Tetapiuntuk urusan yang berkaitan dengan kantorDinas Tenaga Kerja, pihak PJTKI sendiri yangmengurusnya. Kecuali bila ke kantor imigrasiharus yang bersangkutan sendiri yang menguruspaspor karena harus membuat foto.
Menurut Farida, selama paspor masihberlaku, ia bisa bekerja lagi di perusahaantersebut dengan mendaftar kembali, malahlebih mudah prosesnya.
I I I. PENUTUP
A. Kesimpulan
� Perekonomian penduduk desa masihrendah disebabkan oleh kondisi wilayahyang tidak memungkinkan untuk mem-peroleh penghasilan yang layak.Sementara itu kesempatan untuk bekerjadi Malaysia sangat mudah, ditambahdengan banyaknya penawaran lapangan
pekerjaan, baik pekerjaan formal maupuninformal. Pekerjaan tersebut tidakmemerlukan keterampilan khusus dan tidakharus melalui seleksi ketat untuk menempatisuatu bidang pekerjaan yang ditawarkanoleh pihak perusahaan.
� Lokasi tempat tinggal mereka lebih dekatdengan perbatasan dan pada lokasitersebut terdapat banyak jalan tembus keMalaysia, yang memungkinkan wargauntuk memilih jalan pintas daripadaprosedur resmi yang memerlukan biayabanyak. Sementara kondisi lokasi yangberada di daerah perbatasan membukapeluang bagi calo tenaga kerja, apalagimereka dapat menjangkau hingga kedaerah-daerah tempat tinggal penduduk.
� Pemerintah telah berupaya membuatperaturan tentang penempatan tenagakerja Indonesia ke luar negeri, tetapitampaknya kondisi di lapangan sangattidak memungkinkan para calon tenagakerja melaksanakan aturan tersebut.
� Perlindungan terhadap TKW belummaksimal, sehingga menjadi salah satupenyebab banyaknya tindak kekerasanterhadap TKW. Disadari atau tidak, TKWkita yang berpendidikan rendah telanjurberada di luar negeri.
� Dari kasus yang terjadi pada para tenagakerja wanita ini, sebenarnya tidaklahterlalu sulit untuk mulai menumbuhkanpenguatan kepada mereka. Penguatanbukan dari orang lain, melainkan justruharus datang dari mereka sendiri. Salahsatu cara menumbuhkan rasa berdayapada TKW, hak sebagai pekerja, danpemahaman eksistensi diri adalah mulaimemberi pengetahuan tentang kesetaraanjender pada mereka agar bisa memahamidirinya sendiri sebagai sosok perempuandan sebagai pekerja.
B. Rekomendasi
Salah satu cara yang dapat dilakukanuntuk memberikan pemahaman sekaligusperlindungan dini, baik terhadap calon tenagakerja wanita maupun mereka yang sudahmenjadi pekerja, adalah dengan memberikaninformasi yang tepat kepada mereka. Mungkin
11
Permasalahan Pekerja Migran di Daerah Perbatasan (Indah Huruswati)
tidak bisa memberikan hal itu secara buku teks,tetapi harus menggunakan media lain yanglebih sederhana, komunikatif, dan mudahdipahami. Salah satu yang mungkin bisa kitagunakan adalah melalui buku cerita ber-gambar berisi berbagai hal tentang negaratujuan, tugas, hak, dan cerita yang bisamenumbuhkan rasa berdaya pada diriperempuan migran.
LAMPIRAN:
Ada sebuah buku yang pernah diterbitkanoleh ACILS yang tampaknya cukup baik untukmenjadi pegangan bagi mereka yang inginbekerja ke luar negeri. Buku ini berupa komik(cerita bergambar) yang dibuat dengan tujuanuntuk memberikan informasi kepadaperempuan-perempuan muda Indonesiatentang cara bermigrasi yang aman. Buku inibukan dimaksudkan untuk mendorong parapembacanya melakukan migrasi, tetapidiharapkan setelah membaca buku ini, merekalebih berhati-hati dan memutuskan untuk tidakpergi mencari kerja sebelum berusia 18 tahun.
Ada beberapa pesan yang dikemukakandalam buku ini, yaitu :
Isi Pesan 1 :
• Jangan pergi mencari kerja sebelumberumur 18 tahun
• Jangan mudah percaya jika ada orangyang menawarkan pekerjaan mudahdengan gaji besar
• Orang yang kamu kenal pun bisa menipukamu
• Jangan membuat keputusan sendiri.Bicarakan rencana kepergianmu denganorangtua
• Jangan biarkan agen/orang lainmemalsukan surat-surat dan data kamu(seperti KTP, paspor, kartu keluarga danlain-lain)
• Simpanlah fotocopy KTP, paspor dan visakamu di tempat yang aman
• Simpanlah nomor telepon dan alamatLembaga/Yayasan, Kedutaan danKonsulat Indonesia yang bisa membantumu
• Jika kamu menemui masalah di luarnegeri, hubungi Kedutaan/Konsulat Indo-
nesia dan selesaikan masalah kamu disana sebelum kamu pulang
• Jika ada yang menipumu, gunakan jalurhukum
• Laporkan kasus kamu pada polisi atauLembaga yang bisa membantu
Isi Pesan 2 :
• Jangan pergi ke luar negeri lewat caratidak resmi maupun tanpa surat-surat asli
• Pastikan kamu berangkat melalui agenPJTKI yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja
• Sebelum menerima tawaran pekerjaan,catat nama, no KTP, telepon dan alamatagen/calo. Simpanlah catatan itu ditempat yang aman
• Catat juga nama perusahaan, telepondan alamat PJTKI dan majikan kamu
• Kamu berhak mendapat perlakuan baikdari agen/majikan meskipun kamu punyahutang padanya
• Selama di luar negeri, usahakan salingberkirim kabar dengan keluargamu di In-donesia
• Pastikan ada anggota keluarga yangmenjemput di Bandara pada waktu kamupulang ke Indonesia
• Kalau kamu menemui masalah ketika tibadi Bandara, segera lapor polisi
• Jangan membawa uang tunai dalamjumlah banyak pada waktu kamu kembalidari luar negeri. Bawalah uang seperlunyauntuk ongkos pulang ke rumah.
Isi Pesan 3 :
• Kamu harus melaporkan kepergian dankedatanganmu kepada kepala desa
• Sebelum berangkat, catatlah nama, noKTP, telepon dan alamat agen PJTKI dancalon majikanmu
• Sebelum berangkat, pelajari bahasa yangdipakai di negara tujuan kamu
• Tanyakan secara rinci tentang segalakondisi di tempat penampungan/pelatihan (termasuk lamanya waktutunggu, serta hak dan kewajiban kamuselama di sana)
12
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 1-14
• Tempat kerja kamu harus aman, tidakboleh ada perlakuan buruk, kekerasanfisik, perkataan kasar dan pelecehanseksual
• Majikan atau agen tidak bolehmemaksamu melakukan pekerjaan yangberbahaya dan tidak kamu inginkan
• Kalau kamu merasa terancam dan beradadalam bahaya, bersikaplah berani dansegera mencari akal untuk menemukanjalan keluar.
Isi Pesan 4 :
• Jangan takut untuk meminta pertolonganpada keluarga, teman, LSM atau oranglain yang kamu percaya
• Tanyakan dengan rinci tentangpekerjaanmu. Usahakan untuk mendapatkontrak kerja secara tertulis
• Simpanlah fotocopy kontrak kerja kamudi tempat yang aman
• Kamu punya hak untuk gaji yang layak,istirahat, cuti dan pulang ke rumah
• Majikan/agen tidak bisa memaksa kamuuntuk terus bekerja
• Jangan takut untuk menyampaikankeinginanmu pada majikan
• Jika kamu mengalami musibah selamabekerja, kamu berhak mengajukan klaimasuransi (ganti rugi).
Selain pesan-pesan tersebut, dalam bukuini juga dilampirkan contoh daftar isian yangharus para TKW isi, sekaligus dimaksudkanuntuk mengingatkan kesiapan mereka sebelumberangkat.
Di halaman belakang buku ini tercantum:
Daftar Lembaga yang bisa menyediakanbantuan dan informasi yang dapat dihubungioleh para TKI/TKW; daftar alamat KantorPerwakilan Indonesia di luar negeri dan daftaristilah-istilah penting. (Sumber: Endro, dkk,2004, Petualangan Wening dan Kawan-kawan,Selalu Ada Jalan Pulang. American Center forInternational Labor Solidarity, Jakarta: ICMC).
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Irwan, ed, 1997. Sangkan Paran Gender. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Biro Pusat Statistik, 1995. Survey Tenaga Kerja Nasional 1994. Jakarta.
Budiman Iskandar, 2004. Dilema Buruh Di Rantau: Membongkar Sistem Kerja TKI di Malaysia. Jogjakarta:Ar-Ruzz Jogjakarta.
Departemen Tenaga Kerja, 1995. Kebijaksanaan Eksport Jasa Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta: DitjenBinapenta.
Endro, dkk, 2004. Petualangan Wening dan Kawan-kawan, Selalu Ada Jalan Pulang. American Centerfor International Labor Solidarity (ACILS), Jakarta: ICMC.
Kamaruddin M. Said, 1995. “Hubungan Perusahaan di Malaysia dan Isu Hak Pekerja”, JSKK.,Akademika, No. 46, Januari.
Kurniawati, Eni, 2004. Meredam Trafficking Perempuan dan Anak di Kabupaten Sambas dalamPembelajaran Drama Pada Siswa SMA. Karya Tulis dalam rangka Lomba Kreativitas Guru tahun2004.
Moore, Henrietta L., 1998. Feminisme dan Antropologi. Jakarta: Proyek Studi Jender dan PembangunanFISIP-UI dengan Penerbit OBOR.
Mosse, Julia Cleves, 1996. Gender dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nitt, 2005. Posisi Perempuan Dalam Dunia Kerja Masih Tersisih. Kompas, Jogya, Sabtu 23 April,hal. 9.
13
Permasalahan Pekerja Migran di Daerah Perbatasan (Indah Huruswati)
Saadawi, Nawal El, 2001. Perempuan dalam Budaya Patriarki. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner, 1997. Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah PengantarStudi Perempuan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Wijono, Nur Hadi, 1997. “Pekerja dan Permasalahannya”, Analisis. XXXVI/No. 4/Juli-Agustus 1997.
BIODATA PENULIS :
Indah Huruswati, Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, BadanPendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial R.I.
14
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 1-14
STUDI KASUS WANITA-WANITA PENAMBANG PASIR DI DESA
LUMBUNG REJO, KECAMATAN TEMPEL - KABUPATEN
SLEMAN
Mukhlis dan Bambang Pudjianto
ABSTRAK
Menyempitnya kesempatan kerja dan kepemilikan tanah di perdesaan, mendorong masyarakatmenciptakan lapangan kerja baru. Para wanita yang tidak memiliki modal, pendidikan, serta keahlianmenyebabkan mereka memilih pekerjaan pada sektor informal. Adapun pekerjaan yang mereka geluti adalahmenambang pasir. Suatu pekerjaan yang semata-mata mengandalkan kekuatan fisik saja. Hal ini ditempuhuntuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Terutama dalam krisis ekonomi yangberkepanjangan yang menyebabkan biaya hidup semakin meningkat.
Penelitian ini mengambil studi kasus yang bersifat deskriptif. Subyek penelitian adalah wanitapenambang pasir di Desa Lumbung Rejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman. Metode pengumpulandata adalah observasi dan wawancara baik kepada subyek penelitian maupun tokoh-tokoh masyarakat.
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ikatan yang kuat diantara sesama wanita penambang. Halini ditunjukkan dengan memberi bantuan kepada penambang yang tidak dapat bekerja. Kuatnya ikatantersebut karena penambang merasa senasib dan seperjuangan. Hubungan yang kuat juga ditunjukkanwanita penambang kepada pembeli material yang lebih sering disebut ”orang mobil”.
I . PENDAHULUAN
Pembangunan yang dilaksanakan selamaini telah membawa perubahan-perubahanyang besar, baik didaerah perkotaan maupundi daerah perdesaan. Khusus untuk daerahperdesaan ditandai dengan semakin me-nyempitnya lahan pertanian. Hal ini disebabkanpertambahan penduduk yang kian meningkatdan perubahan penggunaan lahan pertanianmenjadi permukiman dan industri sementaraluas lahan relatif tetap.
Sektor informal mempunyai peranan yangcukup besar membantu pemerintah dalamupaya menciptakan lapangan kerja. Lapangankerja terutama diperuntukkan bagi yangberpendidikan rendah sehingga dapatmengurangi pengangguran dan meningkatkankesejahteraan keluarga.
Definisi sektor informal sampai saat inibelum dapat dirumuskan dalam bentuk yangbaku. Yang terlihat dalam beberapa literaturditunjukkan ciri-ciri dan sifat sektor informaldimana ciri dan sifat ini menunjuk pada arahyang berlawanan dengan sektor formalsehingga menggambarkan adanya dualismedalam perekonomian. Hidayat (1982) me-
nyatakan bahwa sektor informal mencakup unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekalimenerima proteksi ekonomi dari pemerintah.
Ada 11 ciri usaha sektor informal sepertiyang diuraikan oleh Hernanto de Soto (1991)meliputi :
1) Kegiatan usaha tidak teorganisasi secarabaik karena timbulnya unit usahatidak mempergunakan fasilitas ataukelembagaan yang tersedia di sektorformal.
2) Pada umumnya unit usaha tidak mem-punyai izin usaha.
3) Pola kegiatan usaha tidak teratur baikdalam arti lokasi maupun jam kerja.
4) Pada umumnya kebijakan pemerintahuntuk membantu golongan ekonomilemah tidak sampai pada sektor ini.
5) Unit usaha mudah keluar dan masuk darisub sektor ke lain sub sektor.
6) Teknologi yang digunakan bersifat primitif.
7) Modal dan perputaran usaha relatif kecil,sehingga skala operasional juga relatifkecil.
15
8) Pendidikan yang diperlukan untukmenjalankan usaha tidak memerlukanpendidikan formal karena pendidikanyang diperlukan diperoleh dari pe-ngalaman sambil bekerja.
9) Pada umumnya unit usaha termasukgolongan one man enterprise dan kalaumempekerjakan buruh berasal darikeluarga.
10) Sumber dana modal usaha padaumumnya berasal dari tabungan sendiriatau dari lembaga keuangan yang tidakresmi.
11) Hasil produksi atau jasa terutamadikonsumsi oleh golongan masyarakatkota/desa yang berpenghasilanmenengah.
Kalau diperhatikan secara cermat, ke 11ciri usaha sektor informal di atas hampir semuadimiliki oleh usaha penambangan pasir.Sebagai contoh penambangan pasir bersifattradisional, menggunakan tenaga manusia,tidak memerlukan tingkat pendidikan dankeahlian serta tidak memerlukan perizinan.
Penambangan pasir ada juga yangbersifat modern, menggunakan alat-alat beratdan badan usahanya biasanya berbentukPerseroan Terbatas (PT). Mereka menggunakanalat-alat berat atau buldozer untuk mengerukdan memuat material langsung ke truk. Dengancara seperti ini, pekerjaan jauh lebih mudahserta lebih efisien dari pada menggunakantenaga manusia. Perusahaan penambanganpasir pernah beroperasi di sungai bebeng, desaBakalan, kabupaten Magelang. Namun sudahdi stop pemerintah daerah tingkat II Magelangsetelah di demonstrasi warga masyarakat padapertengahan juli 1998.
Sangat beruntung penambang pasir yangberada di desa Lumbung Rejo karenaperangkat desanya tidak mengizinkanmasuknya alat-alat berat untuk menambangpasir. Pelarangan dimaksudkan untuk me-lindungi penambang tradisional agar tetapdapat bertahan dalam waktu yang relatif lama.Kebijaksanaan seperti ini perlu dipertahankansehingga tidak hanya memberi perlindungankepada penambang tradisional akan tetapiagar sumber alam terhindari dari kerusakanyang lebih parah.
Sulitnya mencari pekerjaan dan me-ningkatnya biaya hidup menyebabkan orangmemutar otak untuk mencari pekerjaanalternatif. Salah satu diantaranya adalahdengan menambang pasir tersebut.
Dewasa ini kehidupan semakin kompleks,penghasilan suami saja dirasakan kurangmencukupi, terutama bagi pekerja yangberpenghasilan kecil. Dalam kondisi seperti ini,wanita mau tidak mau berpartisipasi baik secarasukarela maupun secara terpaksa untukmenambah penghasilan dengan cara bekerja.Pengkajian tentang wanita yang bekerjaterutama penambang pasir merupakan suatufenomena yang menarik. Pekerjaan inimemerlukan tenaga atau fisik yang kuat, baiksewaktu menggali pasir di sungai maupunsewaktu mengangkatnya ke darat. Tidak semuawanita dapat melakukan pekerjaan ini.
Bertitik tolak dari latar belakang yang telahdikemukakan, maka pokok-pokok perma-salahan yang akan diteliti dapat dirumuskansebagai berikut:
1. Bagaimanakah kehidupan sosial ekonomiwanita penambang pasir di desaLumbung Rejo?
2. Bagaimanakah hubungan antara sesamawanita penambang pasir; antara wanitapenambang pasir dengan pembeli; danantara wanita penambang pasir denganmasyarakat sekitar?
Oleh karena itu, maka penelitian inibertujuan untuk memperoleh gambarantentang:
1. Kehidupan sosial-ekonomi wanitapenambang pasir;
2. Hubungan antara sesama wanitapenambang pasir;
3. Hubungan wanita penambang pasirdengan pembeli; dan
4. Hubungan wanita penambang pasirdengan masyarakat sekitar dimanamereka tinggal.
I I . METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian kualitatif ini adalah penelitianlapangan dengan mengambil bentuk studi kasusyang bersifat deskriptif . Metode pengambilan
16
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 15-24
data yang dipakai adalah dengan observasidan wawancara. Metode observasi digunakanuntuk mencari data tentang kehidupan sosialekonomi para wanita penambang pasir daninteraksinya dengan masyarakat sekitar.Sedangkan metode wawancara digunakanuntuk mencari data tentang pemaknaan ataumaksud dari istilah yang digunakan diantarapara wanita penambang pasir.
Populasi
Populasi dalam penelitian ini seluruhwanita penambang pasir, kerikil, batu pasangdan batu pecah yang berdomisili di desaLumbung Rejo, Kecamatan Tempel, KabupatenSleman Semuanya berjumlah 15 orang. Darijumlah tersebut rata-rata usia mereka kuranglebih 47 tahun, yang berusia 55 tahun ke atassebanyak 1 orang, sedangkan yang berusia25-54 tahun sebanyak 14 orang.
Informan
Dari 15 wanita penambang pasir, yangdijadikan sebagai informan penelitian adalahwanita penambang pasir yang telah bekerjaminimal selama sepuluh tahun. Penetapanselama sepuluh tahun tersebut, didasarkanpada pertimbangan bahwa informan memilikiwaktu yang cukup lama untuk memahami danmendalami pekerjaan penambang pasir. Darikriteria tersebut di atas ada lima orang informanyang memenuhi persyaratan.
I I I. GAMBARAN LOKASI
PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Lumbung Rejo merupakan salah satu desadari delapan desa yang terdapat di kecamatanTempel, Kabupaten Sleman. BerdasarkanMonografi desa Lumbung Rejo tahun 1997.Luas desa Lumbung Rejo mencapai 336,3250ha.
Jumlah kepala keluarga sebanyak 2.388,dan mata pencaharian yang paling banyakyaitu tani (714), buruh tani (706). Sedangkanpenambang pasir tetap 40 orang, diantaranya15 orang adalah wanita. Di samping itu adapenambang pasir musiman mencapai 200orang.
Desa Lumbung Rejo secara adminis-tratif juga berbatasan dengan Kabupaten
Magelang, yaitu desa Jagang Lor, kecamatanSalam. Kedua desa itu banyak dipisahkan olehsungai krasak. Sumber air sungai krasak berasaldari gunung merapi, lebarnya kurang lebih 100meter dan bermuara ke kali progo. Pada musimkemarau airnya hanya setinggi lutut orangdewasa. Diatas sungai krasak, terbentangsebuah jembatan yang panjangnya kuranglebih 300 m. Jembatan itu berfungsi untukmenghubungkan kabupaten Sleman dengankabupaten Magelang.
Di dalam sungai krasak terdapat materialyang cukup banyak berupa pasir, kerikil, danbatu pasang yang mempunyai nilai ekonomis.Tidaklah mengherankan apabila sebagianwarga desa Lumbung Rejo menjadikanpenambangan pasir sebagai mata pen-caharian pokok.
Kalau diperhatikan secara seksama, desaLumbung Rejo sangat unik dan menarik. Karenadi bawah jembatan terdapat pasar baik di hulujembatan maupun di hilirnya. Kedua pasar itudihubungkan oleh jalan aspal dibawahjembatan. Adapun barang-barang yang dijualberupa kebutuhan dapur, barang-barangkelontong, bahkan ada toko mas. Sementaradi sungai yang permukaannya agak tinggidan datar, penduduk membuat kolam-kolamikan bahkan tersedia kolam pemancinganikan dengan membayar Rp.1.000 sekalimemancing.
Guna memperlancar pengangkutan ma-terial dan sungai, maka dibuat jalanpenghubung. Jalan ini diurus oleh Bapak Yaminsebagai pemegang HO (Hak Operasional)atas nama dusun. Untuk itu setiap truk yang lewatpada jalan tersebut dikenai biaya sebesarRp.500,-/truk. Ketentuan ini didasarkan ataskerjasama antara desa dengan dinaspertambangan tingkat II Sleman. Dengandemikian biaya tersebut tidak dibebankankepada penambang.
B. Sejarah Penambangan Pasirdi sungai Krasak
Tidak diketahui secara pasti kapan orangmulai menambang pasir di sungai krasak,khususnya lokasi penambangan di desaLumbung Rejo. Namun menurut BapakSuharyana, Staf Kantor Kepala Desa LumbungRejo dan Bapak Sarin (yang merupakanpenduduk asli dan sesepuh desa Lumbung Rejo)penambangan pasir sudah ada sebelum
17
Studi Kasus Wanita-Wanita Penambang Pasir (Mukhlis dan Bambang Pudjianto)
meletusnya G 30 S/PKI. Dengan demikiandiperkirakan telah ada sebelum tahun 1965.Namun menurut perkiraan peneliti, jauh sebelumtahun tersebut penambangan pasir sudah ada.Hal ini dibuktikan adanya bangunan/rumahpermanen yang cukup tua di desa tersebut.
Selanjutnya menurut Bapak Suharyana,pada saat itu (sebelum 1965) mobil/truk belumbisa ke sungai. Dengan demikian penambangmemikul material tersebut ke atas (ke pinggirjalan). Kemudian baru diangkat ke daerahtujuan. Pada saat itu material mudah diperolehcukup mengumpulkan dan mengangkat.Berlainan dengan kondisi sekarang untukmendapatkan material harus dengan menggali.
Seiring dengan meningkatnya permintaanakan bahan material terutama dari Yogyakartadan sekitarnya, maka semakin banyak pulapenduduk menambang pasir, baik penambangtetap maupun penambang musiman. Sekarangpenambangan pasir sudah merupakan bagiandari mata pencaharian penduduk setempat.
IV. HASIL PENELITIAN
A. Kehidupan Sosial WanitaPenambang Pasir
Informan biasanya mengawali aktivitasnyapada sekitar pukul 08.00, yaitu setelah merekaselesai sarapan. Sebab bila mereka bekerjaterlalu pagi, maka akan terasa dingin di dalamsungai. Oleh karena itu mereka sengajamenunggu sampai matahari mulai terasapanas. Untuk menghindari terik matahari,mereka memakai topi lebar yang terbuat daribambu yang dianyam dan mereka memakaikemeja/baju lengan panjang. Adapunperalatan yang dipakai/digunakan adalahberupa sekop, cangkul, linggis, martil danbakul/tenggok. Kegiatan lain yang merekalakukan di sungai adalah mencuci pakaian-pakaian dan yang telah dicuci dijemur di atashamparan pasir, sehingga membuat pakaianlebih cepat menjadi kering.
Keperluan makan siang mereka bawa darirumah dan biasanya mereka makan di sungai.Hal ini dilakukan apabila mereka memburupekerjaan. Namun bila waktu mereka sedangsenggang, mereka pulang ke rumah untukmakan siang. Guna menghindari panasmatahari yang menyengat, mereka mengambilpelepah kelapa, lalu ditancapkan ke tanah
dengan kemiringan kurang lebih 45 derajatmenghadap ke barat, pelepah kelapa iniberfungsi sebagai pondok.
Tidak setiap hari mereka belanja ke pasar,sebab kadang-kadang ada pedagang sayurkeliling yang melintas di sungai dari dan ke desaJagang Kidul, desa yang bersebelahan dengandesa Lumbung Rejo. Jadi mereka cukupmenghadang penjual sayur keliling danmembeli sesuai dengan kebutuhan mereka.Aktivitas mereka biasanya berakhir kurang lebihpada pukul 16.30 WIB.
B. Hubungan Antara Sesama WanitaPenambang
Berdasarkan keterangan BapakSuharyana, staf kantor kepala desa LumbungRejo, jumlah penambang tetap berjumlah 40orang, diantaranya 15 orang adalah wanita.Sedangkan penambang musiman mencapailebih kurang 200 orang para penambang,khususnya penambang tetap, masing-masingtelah memiliki lokasi penambangan sendiri.Apabila seorang penambang telah menguasai/menempati suatu lokasi, maka penambang laintidak akan menambang di dekat lokasi tersebut.Jarak lokasi antara satu penambang denganpenambang lain sekitar radius 20 meter.Ketentuan itu memang tidak diatur secara tertulis.Namun menurut penuturan ibu Mar ketentuanitu sifatnya lebih merupakan kebiasaan yangsudah berlangsung lama dan sama-samadisepakati dan dipatuhi.
Lokasi penambangan sebagian me-rupakan milik warga dan sebagian merupakantanah kas desa (tanah bengkok) yang dilandabanjir pada masa lalu. Interaksi sosial antarasesama penambang cukup akrab dan berjalanharmonis. Hal ini dapat dibuktikan daripengamatan peneliti di lapangan. Di manapada saat seorang penambang istirahat tengahhari maka ia memanggil temannya/penam-bang yang lain untuk istirahat bersama sambilmenawarkan bahwa ia membawa singkongrebus dan air minum. Pertentangan danbenturan-benturan diantara mereka tidak ada.Hal ini disebabkan diantara sesama merekamasih ada hubungan kekeluargaan dan merekahidup bertetangga.
Rasa kebersamaan mereka sangat tinggi,kalau misalnya salah seorang penambang tidakdatang/bekerja, maka penambang yang lainakan menanyakan kepada temannya yang lain
18
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 15-24
apa penyebab dan halangannya. Merekamerasa senasib dan seperjuangan sehinggaapabila ada temannya yang sakit dan tidakdapat bekerja maka mereka mengumpulkanuang bersama-sama untuk digunakan bagikeperluan dan biaya berobat temannya yangsakit. Namun dalam hal mencari materialmereka memilih bekerja sendiri-sendiri daripadasecara bersama-sama. Alasannya karenakemampuan mereka tidak sama sehingga akansulit membagi hasil secara proporsional.
C. Hubungan Penambang denganPembeli
Dalam menjual hasil tambangannya, parapenambang tidak perlu mencari pembeli.Mereka cukup menunggu pembeli datang kelokasi penambangan sambil mereka bekerja.Para pembeli juga tidak secara langsungdatang ke lokasi tetapi cukup memesan melaluisupir truk. Pembeli tidak hanya dari sekitarSleman saja tetapi juga dari Yogyakarta. Supirtruk bertindak atas nama pembeli karena diadipercaya memegang uang yang akandigunakan untuk membayar material tersebut.Supir truk memiliki dua orang kenek yangbertugas memuat bahan material ke truk danmembongkar muatan di tempat si pembeli.
Dalam melaksanakan pekerjaannya, supirtruk mendapat upah Rp.10.000,- per trip.Sedangkan masing-masing kenek mendapatRp. 5000,- per trip. Mereka dapat mencapaitiga sampai empat trip dalam satu hari dengancatatan material yang akan diangkut cukuptersedia. Sedangkan untuk pemilik trukmendapat Rp. 40.000,- per trip, sudahtermasuk biaya pembelian bahan bakar solar.Tidak jarang ”orang mobil” hanya mendapatsatu sampai dua trip dalam sehari karenasepinya material yang mau diangkut.
Hubungan antara penambang dengansupir serta kenek sudah lama berlangsung danberjalan dengan akrab. Hubungan itu tidakhanya terbatas dalam hubungan jual beli tetapilebih jauh meliputi hubungan sosial. Sebagaicontoh apabila ada keluarga supir atau kenekatau sebaliknya yang mendapat musibahseperti meninggal, mereka saling melayat.Kebetulan para kenek tinggal di desa-desa yangberdekatan dengan desa Lumbung Rejo, sepertidesa Merdikorejo, Margorejo dan Jagang Lor.
Bila ada peristiwa-peristiwa kebudayaanyang diadakan oleh penambang seperti
selamatan dan sunatan, mereka selalumengundang para supir dan kenek yang telahmenjadi langganan mereka untuk menghadiriacara yang mereka adakan. Kondisi-kondisiyang telah disebutkan di atas sudah lamatercipta diantara penambang dengan supir dankenek.
Demikian juga dalam penentuan hargamaterial, para supir mengikuti sesuai denganharga pasaran. Kesepakatan harga antarapenambang dengan pembeli kelihatannyatidak ada masalah karena mereka telahmemiliki harga yang standar pada masa itu.Untuk saat ini harga material adalah sebagaiberikut :
a) Pasir dijual dengan harga Rp. 16.000,-per truk
b) Kerikil dijual dengan harga Rp. 22.000,-per truk
c) Batu pasang dijual dengan hargaRp. 25.000,-
d) Batu split (batu pecah) dijual sehargaRp. 200,- per tomblok (bakul).
Dalam menjual material, tugaspenambang hanya mengumpulkan material disuatu tempat yang dilalui oleh truk. Sedangkanmemuat material ke truk adalah tugas ”orangmobil” dan penjual tidak bertanggung jawabdalam tugas memuat. Pembelian dilakukansecara tunai dan transaksi dilaksanakan dilokasi penambangan. Dalam transaksi tidakdikenal istilah ”ngebon” atau bayar belakangatau ”BB”.
Dikenal pula pembelian material secara”JUM-JUMAN”. Pembelian secara jum-jumanartinya membeli material kepada dua orangatau lebih untuk mencukupi satu truk perhitunganpembayaran material diserahkan kepadakenek. Merekalah yang menaksir jumlah mate-rial dari masing-masing penambang sekaligusmenentukan jumlah uangnya.
Sebenarnya penambang lebih senangmenjual materialnya bila jumlahnya telahmencukupi satu truk. Namun demi membantu”orang mobil” yang sudah terlanjur datang kelokasi maka mereka bersedia menjual secara”jum-juman”. Hal ini menunjukkan bahwadiantara mereka telah terjalin hubunganyang akrab secara emosional karenamereka menyadari bahwa mereka salingmembutuhkan.
19
Studi Kasus Wanita-Wanita Penambang Pasir (Mukhlis dan Bambang Pudjianto)
D. Hubungan Penambang DenganMasyarakat
Keseluruhan wanita penambang pasirmerupakan anggota komunitas desa LumbungRejo merupakan bagian yang integral darimasyarakat itu sendiri. Walaupun pekerjaanmereka berbeda dengan warga yang lainseperti petani dan pedagang namun merekadapat berinteraksi secara normal dan tidakterisolir. Memang diakui bahwa ada stratifikasisosial di dalam masyarakat. Namun perbedaanstatus sosial tersebut tidaklah menghalangipenambang berkomunikasi dengan warga lain.Ini dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatansosial kemasyarakatan yang diikuti oleh ibu-ibupenambang pasir. Kegiatan-kegiatan tersebutantara lain :
1. Mereka berperan serta dalam kegiatan-kegiatan, yang dilakukan oleh PKK tingkatdesa, seperti kelompok dasawisma setiaphari jumat pagi. Untuk menghadirikegiatan tersebut mereka menundakegiatan menambang pasir dan merekabekerja kembali setelah kegiatan PKKselesai. Tentunya kegiatan dilaksanakandengan anggota masyarakat lain secarabersama-sama.
2. Dalam peristiwa-peristiwa budaya, merekaselalu diundang dan dilibatkan dalamberbagai kegiatan. Mereka selaludiundang dalam berbagai acara seperti;perkawinan, upacara kehamilan tujuhbulan (mitoni), menyambut kelahiran padahari ke lima (sepasaran), upacarakelahiran pada hari ketiga puluh lima(selapanan) dan upacara sunatan.
Demikian pula dalam peristiwa kematian,mereka selalu hadir baik yang terjadi padatetangga maupun warga di sekitarnya.
Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, merekasering diminta untuk membantu kelancaranacara tersebut. Misalnya diminta untuk ikutmemasak, seperti yang sering dikerjakan olehibu Mar dan ibu Mur. Mereka mengerjakannyadengan senang hati dan tanpa mengharapkanupah. Mereka sadar bahwa dengan adanyakegiatan tersebut pekerjaan mereka akantertunda. Tetapi mereka juga menyadari bahwahidup bukan hanya semata-mata mencari uangkarena membina hubungan sesama manusiajuga sangat penting.
V. ANALISIS KEHIDUPAN SOSIAL-
EKONOMI PENAMBANG PASIR
Swasono (1986) mengemukakan bahwasektor informal dalam studi pembangunan dinegara dunia ketiga adalah karena timbulnyamasalah kemiskinan perkotaan akibat tidakcukup tersedianya lapangan kerja di daerahperkotaan karena penawaran tenaga kerjamelebihi permintaan dari kebutuhan di sektorformal.
Kondisi seperti yang disebutkan diatasmenurut hemat peneliti tidak hanya terjadi didaerah perkotaan saja tetapi bisa juga terjadidi daerah pedesaan. Terbatasnya lahan disektor pertanian dan perkebunan, khususnya dipulau Jawa serta sulitnya lapangan kerja disektor industri memaksa masyarakat untukmenciptakan lapangan kerja baru. Lapangankerja disesuaikan dengan potensi yang ada.Khusus di desa Lumbung Rejo, potensi yang adadiantaranya penambangan pasir.
Bahkan menurut Miftah Wirahadikusumah(1991), kehadiran sektor informal bukan lagimerupakan fenomena yang bersifat sementaratetapi sudah menjadi ciri yang dominan didalam keadaan ekonomi masyarakat lapisanbawah di dunia ketiga. Kelihatannyapenambangan pasir sebagaimana yangditemukan di Lumbung Rejo bukan lagipekerjaan yang bersifat sementara. Sebagaicontoh informan mbah sudah menggelutinyasejak tahun 1970 (28 tahun), Bu Semi sejak1978 (20 tahun), Bu Ayu sejak 1982 (16 tahun),Bu Mur sejak 1983 (15 tahun), dan bu Marsejak tahun 1978 (20 tahun). Dari hasilwawancara penulis, kelihatannya empat oranginforman tidak ada rencana lagi untukmeninggalkan pekerjaannya. Karena merekamenyadari sulitnya mencari pekerjaan lain.Sedangkan bu Mur masih ingin alih pekerjaankalau ada yang lebih baik.
Ada dua faktor penting yang perludifahami mengenai latar belakang keterlibatanwanita dalam angkatan kerja. Pertama, wanitamemasuki angkatan kerja dan memilih untukbekerja dan berkaitan dengan eksistensinyakarena memiliki tingkat pendidikan danketerampilan yang lebih tinggi. Dengan bekalpendidikan dan keterampilan, berartimempunyai peluang untuk meraih pendapatanyang lebih baik. Kedua, wanita yang bekerjaberasal dari kelompok/kategori berpen-
20
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 15-24
dapatan rendah. Rendahnya pendapatankarena tingkat pendidikan yang lebih rendahpula. Dengan alasan ekonomi pula parawanita mengerjakan semua jenis pekerjaandemi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
Apabila kita perhatikan hasil observasipenulis seperti yang dikemukakan, diperolehsuatu gambaran bahwa wanita penambangpasir termasuk pada kategori kedua. Betapatidak, wanita tersebut pada umumnya tidakbersekolah. Kalaupun ada yang pernahsekolah, paling tinggi tingkat SMP yaitu informanibu Mur (itu pun tidak tamat). Ketidakmampuanmereka mengenyam pendidikan yang layakkarena orangtua mereka kurang mampumenyekolahkan anaknya sebagai akibat tingkatpendapatan yang rendah. Demikian juga suamimereka, sebagian adalah buruh tani, petanipenyewa, dan pekerja tidak tetap. Dengankondisi seperti ini tuntutan untuk bekerja bagiwanita, merupakan sesuatu yang tidak dapatdihindarkan.
Biasanya pekerjaan dibedakan ber-dasarkan jenis kelamin. Walaupun pembedaanitu tidak selalu tepat. Sebagai contoh, pekerjaanmenata rambut dan memasak (seperti di hotel)diasosiasikan dengan pekerjaan wanita. Padahal pekerjaan itu banyak juga dilakukan olehlaki-laki. Dalam hal ini lebih tepat kita menyebutistilah gender. Seperti yang dikemukakan olehMoore (1988, 1994 : 10), gender diartikansebagai konstruksi sosio kultural yangmembedakan karakteristik maskulin danfeminim. Gender berbeda dengan seks ataujenis kelamin laki-laki dan perempuan.
Selanjutnya Susilastuti (1993 : 30),menyebutkan jenis kelamin laki-laki seringberkaitan erat dengan gender maskulin danjenis kelamin wanita berhubungan erat dengangender feminim, kaitan antara jenis kelamindengan gender bukanlah merupakan korelasiyang absolut. Hal ini karena yang dianggapmaskulin dalam suatu kebudayaan bisadianggap feminim dalam budaya lain.
Menurut BPS (dalam hidayat, 1996) enamdari sepuluh pekerja wanita di sektor informalmencari nafkah sebagai penerima upah.Sedangkan sisanya sebagai wiraswasta baikyang mandiri maupun yang dibantu olehanggota keluarga. Hal tersebut disebabkanoleh keterbatasan modal, keterampilan, kurangpengalaman dan rendahnya pendidikan. Ataudengan kata lain kategori maskulin atau
feminim tergantung kepada konteks sosialbudaya setempat. Sebagai contoh dapatdikemukakan bahwa bagi wanita Bali menjadiburuh bangunan dan jalan adalah sesuatu halyang sudah biasa. Sementara bagi wanita sukuMelayu Jambi hal tersebut adalah sesuatu yangtidak biasa. Dalam konteks menambang pasir,bagi wanita di jawa kelihatannya bukanlahsesuatu yang baru. Artinya pekerjaan tersebutsudah dapat diterima sebagai bagian dari matapencaharian tanpa melihat jenis kelaminnya.Hal ini dapat dibuktikan bahwa sepanjangsungai krasak dan sungai bebeng, para wanitabanyak menambang pasir.
Sejalan dengan kehidupan yang semakinsulit, semakin banyak wanita yang bekerja tanpamelihat jenis pekerjaannya. Sebagai contoh,seperti yang dilihat peneliti di pasar Beringharjo,dan shopping centre, hampir semua kuli barang/kuli gendong adalah wanita. Demikian jugaburuh bangunan wanita seperti yang penelitilihat di IAIN Sunan Kalijaga, bahkan wanitapenjual koran. Fenomena ini menunjukkanbahwa dalam memilih jenis pekerjaan sekarangtidak lagi ada pemisahan secara jelas antarapekerjaan laki-laki dengan wanita.
Dilihat dari segi pendapatan, penghasilaninforman relatif kecil. Sebagai contoh informanmbah hanya memperoleh Rp. 1.200 sampaidengan Rp. 1.400 per hari, atau sebesarRp. 36.000 sampai dengan Rp. 42.000 perbulan. Itu pun kalau mbah bekerja secarapenuh. Mbah mengaku dari penghasilannyabisa menutupi kebutuhannya. Sebenarnya mbahmempunyai dua orang anak dan cucu yangsudah besar. Tetapi ia tidak mau menjadi bebanbagi anak dan cucunya. Selagi dia masihmampu bekerja. Untuk itu semangat yang tinggiserta kemandiriannya patut dipuji, terutama biladibandingkan dengan para pengemis yangberkeliaran di tempat-tempat strategi diYogyakarta. Dimana dari segi fisik mereka masihmampu untuk bekerja.
Dari kelima informan, maka yang palingbesar penghasilannya adalah ibu Ayu yaituantara Rp. 5.000 sampai dengan Rp. 6.000per hari. Itu pun karena dibantu suaminya setiaphari. Suaminya memang tidak mempunyaipekerjaan lain. Oleh karena itu ia selalu ikutmenggali dan menambang pasir bersamaistrinya. Penghasilan itu digunakan untukmenghidupi dan menyekolahkan keduaanaknya.
21
Studi Kasus Wanita-Wanita Penambang Pasir (Mukhlis dan Bambang Pudjianto)
Menurut teori Neo Klasik yang di-kemukakan oleh Anker dan Hein (1986),(dalam Nasikun, 1990 : 3) bahwa keluargamengalokasikan sumber daya mereka diantaraanggota-anggota keluarga di dalam cara yangrasional, yang pada gilirannya mengakibatkananggota keluarga wanita memperoleh investasihuman capital yang lebih sedikit dibandingkandengan yang dialami oleh anggota keluargalaki-laki. Konsekuensinya, dengan human capi-tal yang rendah (terutama pendidikan, latihandan pengalaman bekerja) yang rendah makatingkat produktivitas wanita rendah pula. Apayang dikemukakan teori ini tidak hanyamencakup produktivitas pada sektor formaltetapi termasuk juga sektor informal. Tidakadanya atau rendahnya tingkat pendidikan danlatihan yang mereka miliki menyebabkanmereka bekerja pada pekerjaan yang padattenaga yang pada gilirannya menyebabkantingkat produktivitasnya rendah dan akibatnyatingkat penghasilannya rendah. Informan mbahberpenghasilan Rp.1.200 sampai dengan Rp.1.400 per hari, informan bu Semi Rp. 2.500sampai dengan Rp. 3.000, bu Ayu bersamasuami Rp. 5.000 sampai dengan Rp. 6.000,bu Mur Rp. 2.500 sampai dengan Rp. 3.000dan bu Mar berpenghasilan antara Rp. 2.750sampai dengan Rp. 3.750.
Mereka jarang bekerja satu bulan penuh,hambatannya baik karena ada kegiatan desamaupun karena mereka istirahat untukmemulihkan stamina. Dari apa yang disebutkandiatas penghasilan mereka termasuk dalamkategori penghasilan rendah. Namun yang jelassudah dapat meringankan beban ekonomikeluarga.
Kelima informan mengaku harus pandai-pandai membelanjakan uangnya agar bisamencukupi kebutuhan keluarga. Apalagisekarang harga kebutuhan pokok semakinmembumbung dan hampir tak terkendali.Mereka belum mampu untuk menyisihkanpenghasilannya untuk ditabung. Keadaan parawanita penambang dapat dikategorikan padamasyarakat yang berpenghasilan rendah.Penghasilan mereka hanya mencukupi untukmenutupi kebutuhan sehari-hari. Apabila merekatidak bekerja dalam beberapa hari misalnyakarena sakit, maka mereka sudah kesulitan untukmemenuhi kebutuhan hidupnya. Rendahnyatingkat pendapatan wanita karena wanitaberada pada posisi yang kurangmenguntungkan. Seperti yang dikemukakan
Scott (1986, dalam Anker dan Hein), secarakeseluruhan, wanita menonjol dalam industriyang padat tenaga, pekerjaan yang unskilleddengan tidak adanya jaminan kedudukan, danupah yang lebih rendah. Sementara laki-lakiterkonsentrasi dalam pekerjaan pada industriyang padat modal, dengan stabilitas yang lebihbesar, upah yang lebih tinggi dan prospek kariryang lebih baik.
Dengan adanya kenyataan sepertiyang dikemukakan di atas, sudah sepantasnyasemua pihak terutama pemerintah memberikankemudahan-kemudahan kepada mereka.Seperti pembebasan biaya berobat dankeringanan-keringanan lain kepada anak-anakyang bersekolah seperti pembebasan uang BP3dan sebagainya. Upaya-upaya seperti ini akandapat mengurangi pengeluaran merekasehingga mereka dapat meningkatkankesejahteraannya. Barangkali persoalan yangmendasar adalah apakah selamanya merekamampu dan sanggup untuk menggali pasir.Pertanyaan ini tentunya sulit dijawab. Tetapipaling tidak untuk saat ini mereka mempunyaipekerjaan untuk menghidupi keluarganya.
Ada satu hal yang menarik dari wanitapenambang ini, yaitu rasa kebersamaanmereka sangat tinggi. Antara sesamapenambang tidak dianggap sebagai saingantetapi dianggap sebagai teman. Hal ini mungkindisebabkan luasnya areal penambangansehingga tidak ada perasaan takut akankehabisan material. Walaupun pekerjaanmereka membutuhkan fisik yang kuat danmenguras tenaga, mereka masih seringbercanda. Seperti pada suatu hari di sungai,saat itu ibu Mar menggenggam sejumlah uang,kemudian ibu Semi lewat dan melirik kepadaibu mar sambil berkata ”wah dhuwite okeh yo”.Sambil tersenyum ibu Mar menjawab ”yo ora,adole JJ”. JJ adalah singkatan ”jum-juman”yaitu penambang menjual material bersama-sama dengan material penambang lain untukmencukupi satu truk. Dengan demikian mate-rial yang dijual masing-masing penambangtidak cukup satu truk dan tentunya uang yangditerima juga lebih sedikit. Ketika penelitimenanyakan mengapa dijual secara jum-juman, ibu Mar menjawab bahwa ia tidaksampai hati melihat ”orang mobil” yang telahterlanjur datang, pulang dengan tangankosong. Oleh karena itu diupayakan mencarimuatannya dengan cara jum-juman.
22
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 15-24
Pada bagian terdahulu, disebutkan bahwaaktivitas mereka dimulai antara pukul 08.00s/d pukul 16.30 WIB. Namun waktu tersebuttidaklah kaku. Kalau mereka mempunyaikegiatan di desa, mereka bisa mempercepatatau memperlambat waktu bekerja. Demikianjuga bila mereka capai atau ada upacarapernikahan, biasanya mereka tidak bekerjasehari penuh. Seperti penuturan bu mar kepadapeneliti bahwa ia diminta tetangga untukmemasak nasi pada upacara perkawinan.Untuk itu ia tidak menambang selama tiga hari.Namun ketika peneliti menanyakan apakahpekerjaan itu diberi upah dia hanya tersenyumdan tidak memberi jawaban pasti.
VI. PENUTUP
A. Kesimpulan
Tingkat pendidikan dan tingkatpendapatan sangat berpengaruh kepadakualitas hidup, dalam hal ini kesejahteraan parawanita penambang tidak memiliki pendidikanyang memadai dan adanya tekanan ekonomi.Sehingga mereka terpaksa bekerja untukmembantu menambah penghasilan keluarga.Dalam hal ini pekerjaan yang mereka pilihadalah menambang pasir sesuai denganpotensi yang dimiliki desa Lumbung Rejo.Mereka memilih menambang pasir karena tidakada pekerjaan lain. Mereka tidak mempunyaisawah dan ladang untuk diolah.
Hubungan sosial antara sesama wanitapenambang sangat akrab dan mempunyairasa kebersamaan yang tinggi. Sesamapenambang tidak dianggap sebagai sainganakan tetapi dianggap sebagai senasib danseperjuangan. Kesamaan pekerjaan membuatikatan diantara mereka semakin kuat. Merekamenekuni pekerjaan menambang karenapenghasilan suami tidak cukup untuk menutupikebutuhan keluarga. Besarnya penghasilanmereka sangat tergantung kepada kemampuanuntuk mengumpulkan material. Semakin banyakmaterial yang dikumpulkan semakin besar uangyang diperoleh.
Interaksi mereka dengan pembeli mate-rial, dalam hal ini diwakili supir dan kenek truk.Pembeli tidak langsung berhubungan denganpenambang. Hubungan itu tidak semata-matadidasarkan atas hubungan jual beli tetapi lebih
jauh telah tercipta hubungan sosial danemosional. Pekerjaan mereka memangberbeda dengan warga masyarakat lain, yangumumnya petani, pedagang, dan pegawainegeri. Namun mereka dapat berinteraksi danbergaul dalam masyarakat sesuai dengan sta-tus dan peran yang mereka miliki. Sehinggaeksistensi mereka sebagai bagian darimasyarakat tetap terpelihara.
B. Rekomendasi
Sehubungan dengan selesainya penelitianini maka diajukan saran-saran sebagai berikut:
1. Bagi pemerintah setempat, perlu adanyapengawasan yang ketat dan arahansecara teknis pada para penambangdalam hal pelestarian lingkungan dandampak yang ditimbulkan dari prosespenambangan tersebut. Hal ini selainuntuk keselamatan para penambang itusendiri juga agar tidak berdampak padarusaknya lingkungan alam sekitar. ApalagiLokasi tersebut sangat berdekatan dengantebing sungai sehingga bila tidakdipertimbangkan dengan matang akanmenimbulkan longsor yang berbahayabagi jiwa para penambang dan rusaknyapermukaan tanah di lokasi penambangan.
2. Hubungan sosial dan emosional yangtelah dibangun dengan baik oleh parapenambang dengan sesama penambangdan lingkungannya perlu terus dibina dandijaga agar tetap kondusif. Hal ini sangatbermanfaat bagi kenyamanan kerja dandukungan sosial yang terjalin akanberimbas pada hasil kerja yang baik sertatimbulnya suatu rasa kebersamaan. Olehkarena itu perlu dibentuk semacampaguyuban atau wahana antar sesamapenambang juga dengan para supir dankenek sebagai pihak yang berhubunganlangsung dalam proses transaksi.
3. Perlu adanya upaya pemberdayaan bagiusaha penambangan, misalnya dengandiciptakannya bapak angkat bagi parapenambang dan pemberdayaan yangberfungsi pengembangan usaha denganmemfasilitasi kebutuhan peralatan danaksesibilitas yang diperlukan olehpenambang.
23
Studi Kasus Wanita-Wanita Penambang Pasir (Mukhlis dan Bambang Pudjianto)
DAFTAR PUSTAKA
Hernanto de Soto, 1991. Masih ada Jalan Lain (Terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
—————————, 1991. Pertumbuhan Ekonomi Bawah Tanah di Peru. Jakarta: Prisma No. 5LP3ES.
Hidayat, 1982. ”Strategi Ketenaga-kerjaan dan Sumber Daya Manusia”, Sumber Daya Manusia,Kesempatan Kerja dan Pembangunan Ekonomi, Jakarta: LPFE UI.
—————————, 1986. Menuju Kebijaksanaan Tepat Guna dalam Menunjang Peranan SektorInformal. Makalah disajikan dalam Komperensi Nasional Pertumbuhan Penduduk, Urbanisasidan Kebijaksanaan Nasional Perkotaan. Jakarta: LPFE UI.
Moore, Henvietta L., 1988. Feminisan and Authropology, Cambridge: Polity Press.
——————————, 1994. Passion for Diffrences Essay in Anthropology on Gender, Cambridge:Polity Press.
Scott, Alison M.E., 1986. “Economic Development Urban Woman’s Work : The Case of Lima Peru”dalam Anker, Richard dan Hein, Cahterine (eb). Sex Inequalities in Urban Employment in The ThirdWorld. London: The Macmillan Press Ltd.
Susilastuti, Dewi H, 1993. “Gender ditinjau dari Perspektf Sosiologi”, dalam Fanzie Ridjal, Lusi Margiyanidan agus Fahri Husein (ed), Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia ,Yogyakarta: Tiara Wacana.
Swasono, SE., 1986. Studi Kebijakan Pengembangan Sektor Informal, Kerjasama antara Pusat PenelitianPranata Pembangunan UI dengan Centre for Instutional Development University of Indonesia.Jakarta:LPFE UI.
Wirahadikusumah, Miftah, 1991. Sektor Informal sebagai ”Bumper” pada Masyarakat Kapitalis. Jakarta:Prisma no.5 LP3ES.
BIODATA PENULIS :
1. Mukhlis, alumni dari Pascasarjana UGM dengan program Psikologi, saat ini menjabatsebagai Kasub TU di Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara. Selain itu, aktifmengajar di perguruan tinggi swasta.
2. Bambang Pudjianto, menamatkan program S1 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Padjajaran Bandung dan memperoleh gelar Magister pada Bidang PsikologiSosial Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada DI Yogyakarta tahun 2000. Selainaktif menulis di media Jurnal dan Informasi Badan Pendidikan dan Penelitian KesejahteraanSosial juga sebagai Tim Pengelola Jurnal Penelitian dan Pengembangan UKS. Sejak tahun1995 mulai aktif mengajar pada beberapa perguruan tinggi swasta di Jakarta. AdapunPenelitian yang pernah dilakukan meliputi permasalahan di bidang kesejahteraan sosialdan psikologi sosial.
24
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 15-24
PEMBENTUKAN PERILAKU PELACURAN BERLATAR TRADISI
DI KABUPATEN PATI DAN JEPARA, JAWA TENGAH
Irmayani
ABSTRAK
Sewaktu seseorang berada dalam lingkungan sosial dan situasi sosial, yakni ketika terlibat dalaminteraksi sosial maka selalu saja ada mekanisme mental yang mengevaluasi, membentuk pandangan,mewarnai perasaan, dan akan ikut menentukan kecenderungan perilaku seseorang terhadap manusia atausesuatu yang sedang dihadapinya, bahkan terhadap dirinya sendiri. Pandangan atau perasaan seseorangterpengaruh oleh ingatan akan masa lalu, oleh apa yang diketahuinya dan kesannya terhadap apa yangsedang dihadapi saat ini.
Tradisi dan pandangan sebagian masyarakat di kedua daerah tersebutlah yang pada akhirnyamembentuk perilaku pelacuran. Selain itu dipengaruhi pula oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yangserba kekurangan serta keinginan meningkatkan taraf hidup melalui jalan pintas mengakibatkan banyaknyaperempuan-perempuan di kedua daerah tersebut akhirnya terjun sebagai pelacur.
Akibat telah mengakarnya tradisi dan pandangan yang membenarkan adanya praktek pelacuranmaka diperlukan kerja keras pemerintah baik pusat dan daerah serta tokoh-tokoh masyarakat setempatuntuk merubah tradisi dan pandangan tersebut. Penanganan pelacuran hendaknya melalui pendekatanyang disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah setempat, tidak lagi bisa disamaratakan untuk semualokasi praktek pelacuran.
I . PENDAHULUAN
Berbicara masalah pelacuran sama sajadengan membuka masalah paling tua di bumiini. Masalahnya memang lama tetapi selaluterasa baru untuk tetap dibahas dandibicarakan. Sulit untuk menentukan kapanmunculnya perilaku ini, namun bisa dikatakanbahwa sejak adanya norma perkawinan, kononbersamaan dengan itu pula lahirlah apa yangdisebut pelacuran. Mengapa demikian? Sebab,pelacuran dianggap sebagai salah satu bentukpenyimpangan dari norma perkawinan dalammasyarakat. Hubungan seksual antara duaorang jenis kelamin yang berbeda dandilakukan di luar tembok perkawinan sertadengan berganti-ganti pasangan, baikmenerima imbalan uang atau material lainnya,sudah disebut orang sebagai pelacuran.
Kita seolah-olah sudah memiliki semacamkesepakatan sosial dalam memandangkehidupan pelacuran ini. Kita sepakatmemberikan warna hitam terhadapnya.Kehidupan yang berlumpur dan bernoda yangdikutuk masyarakat, tetapi dibalik itu semuanyatanya dunia pelacuran menjanjikan
pemenuhan sejuta impian. Impian yang harusditebus dengan cara yang total oleh wanita-wanita yang ingin mewujudkannya dalammempertahankan hidup dirinya dankeluarganya. Kehormatan diri yang harusdikorbankan untuk dipakai sebagai alat pemuasnafsu seksual laki-laki. Sementara para ahli ilmusosial sepakat mengkategorikan pelacuran inike dalam “patologi sosial” atau penyakitmasyarakat yang harus diupayakan penang-gulangannya. Patologi sosial adalah ilmutentang gejala-gejala sosial yang dianggap“sakit”, disebabkan oleh faktor-faktor sosial.Menurut Kartini Kartono (1981), patologi sosialadalah semua tingkah laku yang bertentangandengan norma kebaikan, stabilitas lokal, polakesederhanaan, moral, hak milik, solidaritaskekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplinkebaikan dan hukum formal.
Aktivitas menjajakan seks atau pelacurandipandang masyarakat sebagai sisi hitamdari kehidupan sosialnya. Warna pandanganini menyebabkan kita melihat semacamkeremang-remangan dalam kehidupanpelacuran. Kiranya terdapat semacam doublestandard dalam memandang masalah ini.
25
Seperti yang dikatakan oleh Dr. J. Verkuyl(dalam Hull, Sulistyaningsih dan Jones; 1997)baik dahulu maupun sekarang kita seringberhaluan dua. “Kita melarang pelacuran,tetapi sebaliknya kita terima juga sebagaisesuatu yang tak dapat dielakkan”. Bagai-manapun pandangan masyarakat terhadapkehidupan pelacuran, kenyataan tetapmembuktikan bahwa pelacuran dalam sistemsosial masyarakat kehadirannya sejak berabad-abad yang lalu dan tiada satu kekuatanpunyang mampu menghapusnya dari mukabumi ini.
Adanya kesepakatan untuk melihatpelacuran sebagai sisi hitam dalam kehidupansosial, tetapi semakin lama kita dihadapkanpada ukuran penilaian sosial yang bergerakdalam ketidakpastian. Apa sesungguhnya yangmembuat kita mengganggap pelacuranberwarna kelam? Apakah penyakit kelaminyang dijangkitkan dari satu tubuh ke tubuh yanglain? Atau pelanggaran daerah yang mengaturlokalisasi pusat perdagangan seks? Ataukahalasan mendasar yang sangat klasik sejakjaman Nabi Musa, yaitu larangan berzina?Tergantung dari sisi mana kita melihat dan sudutpandangan kita itu akan menentukan warnapandangan kita. Namun, perilaku jual-beli sekstersebut tak pernah berubah dari abad keabad.
Berkaitan dengan pelacuran yang ada diPati dan Jepara, maka pertanyaan penelitianini adalah apa yang melatarbelakangiterjadinya praktek pelacuran, mengapa haltersebut berlangsung secara turun temurun, danbagaimana pandangan masyarakat setempatmengenai praktek pelacuran tersebut, sertaupaya apa saja yang dapat dilakukan untukmengurangi praktek pelacuran tersebut.
I I . TUJUAN DAN MANFAAT
A. Tujuan penelitian ini untukmendeskripsikan mengenai :
1. Kegiatan praktek pelacuran dankehidupan sehari-hari masyarakat yangada di Desa Dukuh Seti, Desa KembangKecamatan Dukuh Seti Kabupaten Pati danDesa Blingoh Kecamatan KelingKabupaten Jepara, Jawa Tengah.
2. Sejarah dan penyebab pembentukanperilaku pelacuran di masyarakat setempat
B. Manfaat dari penelitian iniadalah:
1. Memberikan gambaran realitas yangterjadi di masyarakat kedua daerahtersebut.
2. Memberikan masukan bagi penentukebijakan untuk penanganan pelacuran dikedua daerah tersebut.
III. METODOLOGI PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitianini adalah dengan pendekatan kualitatif,berdasarkan tujuannya adalah mendapatkandata tentang suatu permasalahan sehinggadiperoleh pemahaman atau sebagai alat re-checking atau pembuktian terhadap informasiatau keterangan yang diperoleh sebelumnya.
Teknik pengumpulan data melaluiobservasi dengan melihat situasi dan kondisiterutama gambaran fisik baik sarana danprasarana yang ada di kedua desa tersebut;wawancara mendalam dengan seorang“mantan” pelacur dan masyarakat sekitarnya;diskusi kelompok terfokus terhadap kepala desadan tokoh-tokoh masyarakat setempat.
Teknik analisis data yang digunakanbersifat deskriptif yang bertujuan untukmemberikan gambaran mengenai situasi dankondisi kedua daerah tersebut, kehidupansehari-hari masyarakatnya serta kegiatanpraktek pelacuran yang ada di kedua daerahtersebut. Pada analisis akhir dihubungkan antarateori-teori pembentukan perilaku dengankenyataan yang ada di kedua daerah tersebutsehingga diperoleh pemaknaan atas phenom-ena pelacuran tersebut.
IV. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian pelacuran
Pelacuran yang sering disebut sebagaiprostitusi (dari bahasa Latin pro-stituere atau pro-stauree) berarti membiarkan diri berbuat zina,melakukan persundalan, pencabulan danpergundakan (Kartono, 1981). Sementara ituBonger (1950) mengatakan prostitusi adalahgejala kemasyarakatan dengan wanita penjualdiri melakukan perbuatan-perbuatan seksualsebagai mata pencaharian. Sedangkan P.J de
26
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 25-35
Bruine van Amstel menyatakan prostitusi adalahpenyerahan diri dari wanita kepada banyaklaki-laki dengan pembayaran. Sejalan denganitu pula, Iwan Bloch berpendapat, pelacuranadalah suatu bentuk perhubungan kelamin diluar pernikahan dengan pola tertentu, yaknikepada siapapun secara terbuka dan hampirselalu dengan pembayaran baik untukpersebadanan maupun kegiatan seks lainnyayang memberi kepuasan yang diinginkan olehyang bersangkutan.
Sementara itu Commenge mengatakanprostitusi atau pelacuran itu adalah suatuperbuatan seorang wanita memperdagangkanatau menjual tubuhnya, yang dilakukan untukmemperoleh bayaran dari laki-laki yang datang;dan wanita tersebut tidak ada pencahariannafkah lainnya kecuali yang diperolehnyadari perhubungan sebentar-sebentar denganbanyak orang. Sedangkan moeliono me-ngatakan, pelacuran adalah penyerahanbadan wanita dengan menerima bayaran,kepada orang banyak guna pemuasan nafsuseksual orang-orang itu.
Berdasarkan Pola Dasar PembangunanKesejahteraan Sosial tahun 1996, wanita tunasusila adalah seorang wanita yang melakukanhubungan seksual di luar pernikahan dengatujuan untuk mendapatkan imbalan jasa.Perbuatan tuna susila ini bertentangan dengannilai-nilai sosial, norma agama dan sendikehidupan bermasyarakat yang akan meng-ganggu kelangsungan hidup generasi penerussebagai sumber daya manusia yang potensialdalam pembangunan nasional. Dari segiagama, pelacuran merupakan perbuatanperzinahan karena melakukan hubungan seksdi luar pernikahan. Pada umumnya setiapagama menentang perbuatan zina. Dalamagama Islam, larangan berzina tercantumdalam Al Qur’an surat Al Isra ayat 32 dan suratAn Nur ayat 2, didalam ayat-ayat tersebutditekankan, bahwa berzina merupakan dosabesar, perbuatan terkutuk dan sangat keji.
Demikianlah beberapa batasan mengenaiprostitusi atau pelacuran yang dikemukakanoleh para ahli, lembaga pemerintah dan darisegi agama. Jadi, yang dimaksud denganprostitusi, pelacuran, penjajaan seks ataupersundalan adalah peristiwa penyerahan tubuholeh wanita kepada banyak laki-laki denganimbalan pembayaran guna disetubuhi dansebagai pemuas nafsu seks si pembayar, yang
dilakukan di luar pernikahan. Sedangkan yangdimaksud pelacur, wanita tuna susila, wanitapenjaja seks adalah wanita yang pekerjaannyamenjual diri kepada siapa saja atau banyaklaki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsuseksual, atau dengan kata lain, adalah wanitayang melakukan hubungan seksual denganbanyak laki-laki di luar pernikahan dan si wanitamemperoleh imbalan uang dari laki-laki yangmenyetubuhinya. Dalam konteks masalahsosial, pelacuran dibatasi oleh adanya prinsipbahwa perbuatan tersebut dapat merugikanorang banyak. Pelacuran merupakan gejalayang sangat nyata merugikan orang banyak/masyarakat, terutama pelacuran yang dilakukandi tempat-tempat umum atau terbuka.
Sementara itu di Indonesia tidak adasatupun pasal dalam Kitab Undang-UndangHukum Pidana yang secara tegas meng-ancamkan pidana terhadap para pelacur.Hanya ada 3 pasal yang mengancamkanhukuman pidana kepada siapapun yangpencaharian atau kebiasaannya dengansengaja mengadakan atau memudahkanperbuatan cabul dengan orang lain (germo),ini diancam dalam Pasal 296 KUHP. Kemudianyang memperniagakan perempuan (termasuklaki-laki) yang belum dewasa, terdapat dalampasal 297 KUHP. Dan yang terakhir adalahsouteneur, yaitu ‘kekasih’ atau pelindung yangkerap kali juga berperan sebagai perantaraatau calo dalam mempertemukan pelacur danlangganannya dan mengambil untung daripelacuran, diancam dalam pasal 506 KUHP(Soesilo,1964). Sehingga dengan demikian sipelacur sendiri tidak secara tegas diancam olehhukum pidana, karena memang prostitution it-self is not a crime (Winn, 1974).
B. Faktor-faktor penyebab pelacuran
Sebagaimana hasil penelitian yangdilakukan oleh Tjahjo Purnomo dan AshadiSiregar (1983) bahwa faktor-faktor yangmenyebabkan seorang wanita melacurkan diriantara lain :
1. Tekanan ekonomi, karena tidak adapekerjaan terpaksa mereka hidup menjualdiri sendiri dengan jalan dan cara yangpaling mudah
2. Karena tidak puas dengan posisi yangada. Walaupun sudah mempunyaipekerjaan tapi belum puas juga karena
27
Pembentukan Perilaku Pelacuran Berlatar Tradisi di Kab. Pati dan Jepara (Irmayani)
tidak membeli barang-barang perhiasanyang bagus dan mahal
3. Karena kebodohan, tidak mempunyaipendidikan atau intelegensi yang baik
4. Cacat jiwa
5. Karena tidak puas dengan kehidupanseksualnya atau hiperseksual
Menurut Kartono (1981) ada beberapafaktor penyebab timbulnya prostitusi antaralain:
1. Longgarnya peraturan/perundang-undangan yang melarang pelacuranseperti dalam KUHP. PelaksanaanUndang-Undang ini kenyataannya dapatdijadikan sumber pendapatan bagi pihak-pihak tertentu atau dijadikan alat untukmemeras mereka
2. Adanya keinginan dan dorongan manusiauntuk menyalurkan kebutuhan seks
3. Komersialisasi dari seks
4. Dekadensi moral, merosotnya norma-norma susila dan nilai-nilai agama
5. Perkembangan kota-kota, daerahpelabuhan dan industrialisasi yang sangatcepat
6. Bertemunya bermacam-macam kebu-dayaan asing dan kebudayaan daerah.
Sedangkan menurut Simanjuntak (1981)faktor penyebab terjadinya pelacuran antaralain :
1. Faktor sosial
Berlangsungnya perubahan-perubahan sosial yang cepat danperkembangannya tidak sama dengankebudayaan mengakibatkan ketidak-mampuan orang-orang untuk menye-suaikan diri dengan perubahan sosialyang dihadapinya. Seringkali ditemuimasalah sosial yang berbentuk keresahanindividu, tingkah laku abnormal ataumenyimpang, penampilan-penampilanperan sosial yang kurang wajar ataumemadai, serta beberapa identitas lainyang dikatakan menyimpang sepertiterdapat dalam kriminalitas, penyakit men-tal dan sebagainya.
2. Faktor psikologis
Berbagai kelemahan jiwa tertentuyang dialami oleh seseorang baik yangberwujud ketidakstabilan maupun tindakanpenyesuaian diri yang negatif, seringkalibanyak diakibatkan oleh kekecewaan atauterjadinya kepahitan hidup pada saat-saatatau kejadian yang telah lampau dapatmengakibatkan seseorang terjerumusdalam kegiatan pelacuran.
3. Faktor ekonomis
Manusia adalah makhluk sosialyang didalam hidupnya berhubungandengan orang lain. Hal itu dilakukandalam rangka memenuhi kehidupan yaituuntuk mempertahankan kelangsunganhidup dalam lingkungannya. Demikiansebaliknya kondisi lingkungan turutmempengaruhi tindakan-tindakannyadalam berhubungan dengan orang lain.Kondisi lingkungan seperti ini dapatmengakibatkan seseorang menjadipelacur.
4. Faktor biologis
Dengan meningkatnya unsur seorangwanita, maka organ-organ maupunhormon seks akan semakin matang,sehingga dorongan seksnya tidak ter-puaskan dapat mengakibatkan terjerumusdalam kegiatan pelacuran.
5. Faktor-faktor lain
Faktor-faktor lainnya sepertirendahnya tingkat pendidikan, kondisipsiko-seksual yang luar biasa dan hiperseksbanyak menimbulkan seseorang ter-jerumus dalam praktek pelacuran.
C. Teori-teori Pembentukan Perilaku
Perilaku yang merupakan salah satukomponen dalam struktur sikap (komponenkognitif, afektif dan konatif) menunjukkanbagaimana perilaku atau kecenderunganberperilaku yang ada dalam diri seseorang ber-kaitan dengan objek sikap yang dihadapinya.Kaitan ini didasari oleh asumsi bahwakepercayaan dan perasaan banyak mem-pengaruhi perilaku. Maksudnya, bagaimanaorang berperilaku dalam situasi tertentu danterhadap stimulus tertentu akan banyakditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan
28
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 25-35
perasaannya terhadap stimulus tersebut.Kecenderungan berperilaku secara konsisten,selaras dengan kepercayaan dan perasaan inimembentuk sikap individual. Karena itu, adalahlogis untuk mengharapkan bahwa sikapseseorang akan dicerminkannya dalam bentuktendensi perilaku terhadap objek. Pengertiankecenderungan berperilaku menunjukkanbahwa komponen konatif meliputi bentukperilaku yang tidak hanya dapat dilihat secaralangsung saja, akan tetapi meliputi pula bentuk-bentuk perilaku yang berupa pernyataan atauperkataan yang diucapkan oleh seseorang.
Sikap sosial terbentuk dari adanyainteraksi sosial yang dialami oleh individu.Interaksi sosial mengandung arti lebih daripadasekedar adanya kontak sosial dan hubunganantar individu sebagai anggota kelompoksosial. Dalam interaksi sosial, terjadi hubungansaling mempengaruhi diantara individu yangsatu dengan yang lain, terjadi hubungan timbalbalik yang turut mempengaruhi pola perilakumasing-masing individu sebagai anggotamasyarakat. Lebih lanjut, interaksi sosial itumeliputi hubungan antara individu denganlingkungan fisik maupun lingkungan psikologisdi sekelilingnya. Dalam interaksi sosialnya,individu bereaksi membentuk pola sikap tertentuterhadap berbagai objek psikologis yangdihadapinya adalah pengalaman pribadi,kebudayaan, orang lain yang dianggappenting, media massa, institusi atau lembagapendidikan dan lembaga agama, serta faktoremosi dalam diri individu.
Pelacuran dinyatakan sebagai masalahsosial, karena perilaku seks yang tidak sesuaidengan norma-norma masyarakat, moralagama serta merendahkan martabat manusia.Bagaimana seorang perempuan sampaiberperilaku sebagai pelacur berkaitan denganbeberapa teori yang menerangkan tentangperilaku, yaitu :
1. Teori Rangsang Balas (Stimulus ResponseTheory)
Teori ini sering juga disebut TeoriPenguat (Reinforcement Theory) yangdapat digunakan untuk menerangkanberbagai gejala tingkah laku sosial. TeoriPenguat menerangkan tentang sikap (atti-tude), yaitu kecenderungan ataukesediaan seseorang untuk bertingkahlakutertentu kalau ia menghadapi suatu
rangsang tertentu. Salah satu teori untukmenerangkan terbentuknya sikap inidikemukakan oleh Darryl Beum (1964),salah seorang pengikut Skinner. Iamendasarkan diri pada pernyataan Skin-ner bahwa tingkah laku manusiaberkembang dan dipertahankan olehanggota-anggota masyarakat yangmemberi penguat pada individu untukbertingkah laku secara tertentu (yangdikehendaki oleh masyarakat). Dalamteori tersebut, Beum menyatakan bahwadalam interaksi sosial terjadi 2 macamhubungan fungsional, yang pertamaadalah hubungan fungsional dimanaterdapat kontrol penguat (reinforcementcontrol) yaitu jika tingkah laku balas (re-sponse) ternyata menimbulkan penguat(reinforcement) yang bersifat ganjaran (re-ward). Dalam hal ini ada tidaknya ataubanyak sedikitnya rangsang penguat akanmengontrol tingkah laku balas. Tingkahlaku untuk mendapat ganjaran tersebutdisebut tingkah laku operan (operant re-sponse). Sedang hubungan fungsionalkedua hanya terjadi jika tingkah laku balashanya mendapat ganjaran padakeadaan-keadaan tertentu. Teori Belajarmelalui Instrumental Conditioning jugamenerapkan prinsip pemberian hadiah (re-ward) dan hukuman (punishment) terhadapmunculnya respon-respon dari subyek.Respon yang muncul sesuai yangdikehendaki diberi hadiah, sedangkanrespon yang muncul tidak sesuai dengankehendak dikenai hukuman.
2. Teori Belajar Sosial (Social LeaarningTheory) atau Modelling
Teori ini menjelaskan bahwa sikap itudapat terbentuk melalui subyek yangmengobservasi atau melihat kejadian-kejadian atau model-model yang ada disekitarnya. Atau dapat juga dikatakanbahwa pada umumnya orang belajarmenanggapi sesuatu dan meresponnyadengan melihat dari apa yang dilakukanoleh orang lain. Menurut Bandura, bahwatingkah laku itu tergantung atau fungsi darilingkungan yang berinteraksi denganorganisme. Yang dimaksud interaksi disiniadalah saling berhubungan antaralingkungan dan organisme. Antara lingkah
29
Pembentukan Perilaku Pelacuran Berlatar Tradisi di Kab. Pati dan Jepara (Irmayani)
laku, lingkungan dan organisme itusebenarnya satu dengan yang lain salingmempengaruhi.
V. SEJARAH DAN KONDISI
MASYARAKAT DESA
A. Sejarah Pelacuran di Pati danJepara
Adanya praktek pelacuran di Desa DukuhSeti, Desa Kembang Kecamatan Dukuh SetiKabupaten Pati dan di Desa Blingoh,Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, PropinsiJawa Tengah dikarenakan adanya beberapaperistiwa yang terjadi, yaitu adanya pekerjamigran orang-orang Cina yang datang melaluiPelabuhan Juwono yang jaraknya dekat denganDesa Dukuh Seti. Pekerja migran lain adalahdatangnya orang-orang Portugis yang dapatdilihat dengan adanya bangunan BentengPortugis Para pekerja ini lalu tinggal lama didesa itu dan banyak berhubungan denganwanita-wanita di sekitar mereka tinggal dan adapula yang menikahi wanita-wanita tersebut.Selain pekerja migran dari luar negeri jugabanyak terdapat pekerja migran yang berasaldari daerah lain dengan didirikannya pabrikgula, perkebunan karet dan jati. Penyebab laintumbuh suburnya pelacuran sejak adanyakampanye partai politik yang dimulai tahun1972 dimana bila ada pejabat-pejabat yangdatang baik dari kabupaten atau yang lebihtinggi maka gadis-gadis di desa tersebut dimintamenjadi pagar betis upacara-upacara tertentu,tetapi kemudian atas perintah Kepala Desa jugadijadikan pemuas nafsu pejabat-pejabat tadi.Kejadian tersebut berlangsung terus danakhirnya mereka menjadi pelacur karena adaiming-iming mendapat uang banyak. Selainitu adanya cerita rakyat setempat yang diyakinisebagai suatu kisah terjadinya praktek pelacuranadalah kisah Ki Brojo Seti. Ia seorang tokohsakti dimana diyakini bahwa istri Ki Brojo Setiini berselingkuh dengan salah seorang muridnyadan akhirnya diketahui oleh Ki Brojo Seti. Sejaksaat itu Ki Brojo Seti bersumpah bahwa parawanita di desa tersebut akan menjadi pelacur(Hull, Sulistyaningsih dan Jones, 1997).
B. Kondisi Fisik Desa
Kondisi fisik desa baik sarana transportasi,sarana ibadah, sarana pelayanan umum yang
lain, dan rumah-rumah penduduk tertatadengan baik. Dari informasi yang diterimadapat diketahui ada perbedaan kondisi rumahpara pelacur dengan penduduk desa biasayang terlihat secara nyata bahwa rumah-rumahpara pelacur terlihat lebih mewah dengan lantaikeramik, bentuknya hampir sama yaitu bergayaSpanyol, ada yang mempunyai parabola,mobil, isi rumah modern dan lengkap. Informasilain adalah adanya satu rumah milik mbak Yyang terlihat paling megah dan mewah dandianggap paling senior dan terkaya dalam halmateri dan dapat pergi haji bersama suaminya.Sedangkan penduduk lain terlihat seperti rumah-rumah penduduk pedesaan yang sederhanadengan lantai biasa (bukan keramik) danbahkan ada yang masih berlantai tanah,dinding dari bambu serta beratap gentengbiasa.
Rumah-rumah ibadah baik Mesjid, Gerejaatau Kuil banyak terlihat di desa-desa tersebut.Umat muslim daerah tersebut kebanyakananggota Nahdatul Ulama (NU), anak-anakbelajar mengaji dan agama pada guru-gurumengaji atau kyai yang ada di daerah tersebut.Informasi yang diterima bahwa anak-anak didaerah ini lebih paham huruf Arabdibandingkan huruf Latin. Tetapi walaudemikian pendidikan formal yang ada cukupmemadai dengan banyaknya sekolah-sekolahbaik tingkat dasar, menengah maupun tingkatatas. Kerukunan antar umat beragama cukupterlihat dengan baik diantara umat Muslim,Kristiani dan Budha, dimana setiap perayaanhari-hari besar keagamaan berjalansebagaimana biasanya.
Informasi menarik lainnya adalah adanyasatu Mesjid yang dibiayai pembangunannyaoleh para pelacur di Desa Blingoh. Selain itupada saat menjelang lebaran para pelacuryang bekerja di kota-kota besar akan pulangke desa dengan membagikan hadiah berupapakaian dan makanan yang dibawa denganmobil truk lalu diberikan keadaan masyarakatsetempat yang kurang mampu. Kehidupansosial masyarakat berjalan dengan baik,adanya saling menolong antara yang mampudan yang kurang mampu, komunikasi diantaramereka juga tidak mengalami kesulitan. Selainturut membangun rumah ibadah, mereka jugaturut membantu pembangunan fisik desa sertaturut menyumbang apabila ada perayaan hari-hari besar, misalnya perayaan 17 Agustus.
30
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 25-35
C. Perilaku Masyarakat Desa
Informasi yang diterima dari beberapainforman penting menggambarkan adanyabeberapa perilaku masyarakat desa yang terkaitdengan praktek pelacuran, antara lain :
1. Bahwa laki-laki di desa tersebut banyakyang malas bekerja lalu mereka menikahiwanita yang berpotensi secara fisik untukmelacur dan istrinya disuruh melacur dandari situlah ia mendapatkan uang, adapula laki-laki yang kerjanya mencariwanita-wanita yang mau disuruh melacurlalu dikirim ke Jakarta dan dari mengirimwanita-wanita tersebut kepada mucikari iamendapatkan uang. Wanita yang menjadipelacur sebelumnya menikah terlebihdahulu dan pada waktu menikahkebanyakan berusia remaja atau sekitarbelasan tahun. Setelah menikah ada pulayang sampai mempunyai anak, kemudianmenjadi pelacur baik di desa merekasendiri atau ke Jakarta.
2. Ada dua jenis pelacuran di ketiga desatersebut (Desa Dukuh Seti, Desa Kembangdan Desa Blingoh), yaitu mereka yangberada di Jakarta tetapi sewaktu-waktupulang dan membangun rumah, membelisawah serta barang-barang mewahperabotan rumah tangga, dan ada pulayang menetap di desa. Denganpenghasilan dari melacur, kehidupansosial ekonomi mereka berubah 180derajat dari yang hidupnya hanya cukupuntuk sehari-hari sampai mempunyaimateri yang cukup dan bisa membelibarang-barang mewah yang sebelumnyatidak mereka miliki. Bagi pelacur yangmenetap di desa mempunyai kebiasaan,menurut masyarakat desa memakai istilah“sandal” yaitu apabila di depan rumah/pintu ada sandal tergeletak itu berartibahwa istri dari pemilik rumah tersebutsedang menerima “tamu” laki-laki lain.
3. Terdapat persaingan antar pelacur dalammengejar materi terutama rumah danperabotan rumah tangga yang tidak mauketinggalan jaman, bentuk rumah dandekorasi ada kesamaan. Dengan adanyapersaingan ini mendorong merekamencari uang sebanyak-banyaknya agartidak ketinggalan dari pelacur lain dalamhal materi.
4. Wanita-wanita pelacur yang beraktivitas diluar desa, misalnya Jakarta, apabilamereka kembali ke rumah maka menjadimilik suami sepenuhnya dan tidak melacurselama berada di rumah. Namun demikianbanyak pula terjadi perceraian yangdisebabkan karena suami ketahuanberselingkuh dengan wanita lain dan maumenjadikan wanita simpanannya sebagaiistrinya.
5. Wanita-wanita pelacur yang berhasil di luardaerah akan membawa teman-temanatau saudara untuk dibawa ke kota dandijadikan pelacur. Hal ini karena tergiuroleh berlimpahnya harta dari hasil melacur.Praktek seperti ini telah mulai ramai sejaksekitar tahun 1970-an dikarenakankehidupan mereka di desa yang miskindan kecintaan terhadap materi sehinggamenjadikan jalan pintas karena tidak maubekerja keras tetapi ingin hidup mewah.
Selain itu ada beberapa pandangan/pendapat baik pelacur maupun suami merekamengenai perilaku pelacuran yang merekalakukan, yaitu :
1. Wanita-wanita pelacur yang mempunyaianak tidak menginginkan anaknyamenjadi pelacur juga, bahkan merekamenyekolahkan anaknya di luar desamereka, biasanya mereka berhentimelacur apabila anak-anak mereka sudahduduk di bangku SMU. Selain itu bagi laki-laki yang sering menggunakan jasapelacur akan menghentikan perilaku iniapabila anak-anak mereka sudahmenjelang dewasa atau setingkat SMUkarena takut ketahuan oleh anaknya.
2. Para wanita pelacur dan sebagainmasyarakat desa yang menganggapbahwa pelacuran itu tidak melanggarnorma agama karena mereka merasatidak merugikan orang lain dengan alasanmereka berbuat demikian karena dibayar.Sebagian laki-laki di desa tersebut jugaberanggapan bahwa konsep pernikahandan keperawanan tidak penting artinyakarena memang tidak memahaminya.Bagi mereka yang penting adalahdapat berhubungan seksual denganmemuaskan.
3. Wanita-wanita pelacur banyak yangmerasa berhutang budi kepada mereka
31
Pembentukan Perilaku Pelacuran Berlatar Tradisi di Kab. Pati dan Jepara (Irmayani)
yang justru menjerumuskan ke praktekpelacuran dengan alasan sejak merekamenjadi pelacur kehidupan sosialekonomi keluarganya menjadi me-ningkat dan dapat menghidupi seluruhkeluarganya.
VI. ANALISA DATA
A. Tradisi dan Perkembangan Pelacuran
Asal usul pelacuran di daerah Pati danJepara bukan saja dimulai sejak adanyapekerja migran tetapi jauh sebelumnya yangapabila ditelusuri kembali hingga ke masakerajaan-kerajaan Jawa dimana perdaganganperempuan pada saat itu merupakan bagianpelengkap dari sistem pemerintahan feodal.Para raja tersebut seringkali dianggapmenguasai segalanya, tidak hanya tanah danharta benda tetapi juga nyawa hamba sahayamereka, semua orang diharuskan mematuhinyatanpa terkecuali. Kekuasaan raja yang takterbatas ini juga tercermin dari banyaknya seliryang dimilikinya. Beberapa orang selir memangputri bangsawan tetapi ada juga yang berasaldari masyarakat kelas bawah yang dijual ataudiserahkan oleh keluarganya dengan maksudagar keluarga tersebut statusnya meningkat danmempunyai keterkaitan dengan keluarga istana.Perempuan yang dijadikan selir tersebut berasaldari daerah tertentu yang terkenal banyakmempunyai perempuan cantik dan memikat.Daerah-daerah seperti ini sekarang terkenalsebagai sumber wanita pelacur untuk daerahkota. Menurut Koentjoro (1989) ada 11kabupaten di Jawa, termasuk diantaranyaadalah Pati dan Jepara di Jawa Tengah.
Makin banyaknya jumlah selir yangdipelihara, bertambah kuat posisi raja di matarakyatnya. Hanya raja dan kaum bangsawanyang mempunyai selir. Mempersembahkansaudara atau anak perempuan kepadapejabat tinggi lainnya merupakan tindakanyang didorong oleh hasrat untuk memperbesardan memperluas kekuasaan. Kondisi seperti initelah menjadi salah satu landasan dimana nilai-nilai perempuan sebagai barang daganganyang diperjual-belikan untuk memenuhi tuntutannafsu laki-laki dan untuk menunjukkan adanyakekuasaan dan kemakmuran.
Dengan adanya sejarah masa lalu yangdemikian dimana banyak pejabat tinggi yangdapat disamakan seperti pada jaman raja-raja
dahulu yang menerima persembahan berupaperempuan-perempuan desa yang diper-sembahkan untuk memuaskan nafsu seksualnyaditambah lagi dengan banyaknya pekerjamigran yang datang ke daerah Pati dan Jeparadapat dikatakan sebagai penyebab adanyapelacuran di daerah ini. Para pekerja migrandengan membawa kebiasaan dan kebu-dayaannya dan menetap lama di daerah initelah menimbulkan interaksi sosial yang dapatberakibat positif dan negatif. Sisi positifnyadapat meningkatkan pendapatan daerahsetempat tetapi sisi negatifnya dapat mem-pengaruhi perilaku masyarakat setempat yangsebelumnya memang sebagai daerahpemasok pelacur menjadi tambah suburdengan kehadiran para pekerja migrantersebut.
B. Kehidupan keluarga pelacur danmasyarakat sekitarnya
1. Kehidupan pelacur dan keluarganya.
Tekanan ekonomi, tingkat pen-didikan yang rendah atau mempunyaiperilaku hiperseksual serta adanya iming-iming mendapatkan uang yang banyakdan mudah telah menjadikan perempuan-perempuan di daerah ini terjangkiti sifatmaterialistis yang menganggap kekayaandan kemewahan adalah segalanyasehingga akhirnya mereka mengambil“jalan pintas” yang tanpa mempunyaiketerampilan apapun yaitu menjadipelacur. Perilaku imitasi kemudian berlakudimana pelacur yang telah mempunyaibanyak uang memamerkan segalakekayaannya lewat barang-barangmewah berupa rumah yang mewahbeserta perabotannya, mobil, antena pa-rabola dan barang-barang mewahlainnya yang dapat membuat perempuanlain menjadi iri dan ingin seperti merekasehingga akhirnya turut terjun menjadipelacur. Perilaku “mengambil jalan pintas”seperti itu tidak saja dilakukan olehperempuan-perempuan daerah tersebut,juga oleh laki-lakinya tetapi dengan caramenikahi perempuan-perempuan yang“berpotensi” untuk dijadikan pelacur dandari hasil istrinya melacur ia mendapatuang. Menurut hasil penelitian Dr. Djuandayang dikutip B Simanjuntak (dalam Hull,Setyaningsih dan Jones, 1997) bahwa
32
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 25-35
yang menyebabkan perempuan dari desamenjadi pelacur adalah karena alasanekonomi daripada yang berasal dari kota.
Sebagaimana diketahui bahwatingkah laku atau aktivitas yang ada padaindividu itu tidak timbul dengan sendirinya,tetapi sebagai akibat dari adanya stimu-lus atau rangsang yang mengenai individuitu. Tingkah laku atau aktivitas itumerupakan jawaban atau responterhadap stimulus yang diterimanya(Woodwarth dan Schlosberg, 1971). Didalam kehidupan sosial, manusia salingberinteraksi antara satu dengan yang lain,saling memahami tingkah laku antara yangsatu dengan yang lain sehingga kemudianterciptalah kehidupan bersama. Perilakuseseorang dalam kehidupan sosialmerupakan stimulus lalu mengadakanreaksi, kemudian tingkah laku reaksi inimenjadikan stimulus lagi bagi orang lain.Menurut Bommer (dalam Sarwono,1995), hidup adalah saling berinteraksi,hidup saling berhubungan yang satudengan yang lain, minimal dua orang,saling mempengaruhi dan menyebabkanterjadinya perubahan sikap dan perilaku.Tingkah laku individu sebagai anggotaberkelompok (dalam kehidupan sosial) itusangat ditentukan oleh keberhasilan/kegagalan di dalam menimbulkan tingkahlaku orang atau di dalam mereaksi tingkahlaku orang lain. Juga dalam “Law of Be-havior” formulasi terakhir menerangkanbahwa perilaku manusia dalamberinteraksi sosial merupakan hasilinteraksi antara situasi sosial denganindividu itu sendiri dan dengan pe-ngalaman kehidupannya sehari-hari.
Dalam hal pembentukan danperubahan sikap, teori belajar melalui “in-strumental conditioning” dengan tokohnyaSkinner. Teori ini menerapkan prinsippemberian hadiah (reward) dan hukuman(punishment) terhadap munculnya respon-respon dari subyek. Respon yang munculsesuai dengan dikehendaki diberi hadiah,sedangkan respon yang muncul tidak sesuaidengan kehendak dikenai hukuman.Selanjutnya teori belajar melalui “modelling”menjelaskan bahwa pada umumnya orangbelajar menanggapi sesuatu danmeresponnya dengan melihat dari apa yang
dilakukan oleh orang lain, baik berupakejadian-kejadian atau model-model yangada disekitarnya.
Iming-iming untuk mendapatkanuang yang banyak dengan cara yangmudah merupakan stimulus yang diterimaseorang perempuan lalu meresponnyadan memutuskan untuk menjadi pelacur.Uang dapat juga merupakan “reward”sehingga perempuan tersebut merasasenang mendapat uang yang banyakyang pada akhirnya membentuk sikapnyauntuk terus menjadi pelacur. Selain itudengan melihat pelacur lain yang berhasilmerupakan “modelling” bagi perempuanlain untuk turut menjadi pelacur, demikianjuga bagi laki-laki yang tidak mempunyaipekerjaan melihat teman-temannyamenikah dengan perempuan yangkemudian dijadikan pelacur dan men-dapat uang dari hasil melacur istrinyasehingga tidak perlu bekerja kerasmenjadikan model bagi laki-laki lain untukberbuat yang sama. Selain itu uang hasilmelacur juga dipakai untuk menghidupikeluarga pelacur, anak, saudara, orangtua sehingga kehidupan mereka tercukupidan mereka merasa senang. Perasaansenang dari orang yang menerima pem-berian uang atau hadiah ini merupakanreward bagi si pelacur untuk terus melacurkarena merasa perilakunya dapatmembuat orang lain senang dan diterimaoleh orang-orang disekitarnya.
2. Kehidupan masyarakat di sekitar pelacur
Sejak jaman raja-raja Jawa, daerahPati dan Jepara dikenal sebagai salah satudaerah sumber wanita pelacur untukdaerah kota, selain untuk daerah kotapraktek pelacuran juga terlihat dikehidupan masyarakat setempat danmasyarakat setempat juga menerimakehadiran dan perilaku melacur tersebut,menerima pemberian mereka berupahadiah pada waktu hari raya, menerimabantuan mereka untuk pembangunandesa, bahkan mendirikan tempat ibadah.Dengan penerimaan ini membuat parapelacur mendapatkan “penguat” darimasyarakat setempat bahwa apa yangmereka lakukan adalah wajar. TeoriPenguat (reinforcement theory) dapat
33
Pembentukan Perilaku Pelacuran Berlatar Tradisi di Kab. Pati dan Jepara (Irmayani)
digunakan untuk menerangkan berbagaitingkah laku sosial tersebut. Salah satu teoriuntuk menerangkan terbentuknya sikap inidikemukakan oleh Darryl Beum (1964)yang juga pengikut Skinner(berpandangan operant). Ia mendasarkandiri pada pernyataan Skinner bahwatingkah laku manusia berkembang dandipertahankan oleh anggota-anggotamasyarakat yang memberi penguatpada individu untuk bertingkah lakusecara tertentu (yang dikehendaki olehmasyarakat).
Kehidupan keagamaan masyarakatdesa berlangsung dengan baik,banyaknya rumah ibadah baik Mesjid,Gereja maupun Kuil ternyata tidakmenjamin akan adanya praktek pelacuran.Yang menjadi masalah adalah bahwamasyarakat setempat tidak menganggappraktek pelacuran yang ada bukan suatumasalah karena dari hasil tersebut dapatmeningkatkan taraf kehidupan mereka.Dalam konteks masalah sosial, prostitusimerupakan gejala yang dapat merugikanorang banyak, tanpa mereka sadaribahwa dengan adanya pelacuran dapatmerusak moral anak-anak. Cara berpikirmereka akan sangat dipengaruhi olehperilaku orangtuanya dan lama-kelamaanakan menganggap bahwa pelacuranadalah hal yang wajar.
Dekadensi moral, merosotnyanorma-norma susila dan nilai-nilaikeagamaan yang terjadi di daerahtersebut merupakan akibat darimelemahnya kontrol sosial masyarakatdan lembaga-lembaga masyarakatdalam menghadapi permasalahanpelacuran di daerah tersebut.Permasalahan ini semakin kompleks danrumit karena pelanggaran norma susiladan keagamaan ini dijadikan matapencaharian dan adanya dukunganmasyarakat yang semakin berkembangterhadap perilaku pelacuran ini.
VII. PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Sejak jaman kerajaan-kerajaan Jawadimana perdagangan perempuan pada
waktu itu merupakan bagian daripelengkap sistem pemerintahan feodal,selain itu daerah Pati dan Jepara sudahterkenal mempunyai perempuan cantik danmemikat yang dijadikan selir raja-raja.Banyaknya pekerja migran dari daerahlain dan datangnya bangsa-bangsa asingyang mendirikan pabrik gula, perkebunankaret dan pohon jati membuat daerahtersebut mengalami perubahan sosial,ekonomi dan budaya, dimana dampaknegatifnya adalah para pekerja migrandapat berhubungan seksual secara bebasdengan perempuan setempat. Padaakhirnya daerah tersebut menjadi terkenalsebagai daerah sumber pelacur untukdaerah kota dan daerah itu sendiri.
2. Dengan memasuki dunia pelacuran,seorang perempuan di daerah tersebutdapat menghidupi keluarganya denganmencukupi bahkan dapat menyumbangpembangunan desa, perayaan hari-haribesar, menyumbang untuk masyarakatkurang mampu bahkan pembangunanrumah ibadah. Laki-laki yang tidakmempunyai pekerjaan dan menikah hanyauntuk mendapatkan keuntungan dariistrinya yang melacur merupakan salahsatu indikator merosotnya nilai-nilai, moraldan agama. Masyarakat justru ada yangmendukung perilaku-perilaku tersebut daninilah faktor penguat kegiatan pelacuranterus berlangsung.
3. Anggapan perempuan di daerah tersebutbahwa kekayaan dan kemewahan adalahsegalanya telah membuat praktekpelacuran semakin subur, dengankenyataan kehidupan mereka bertambahbaik membuat iri perempuan lain danakhirnya juga terjun sebagai pelacur.Persaingan diantara mereka dapat terlihatdari adanya perilaku yang inginmemamerkan kekayaannya melaluirumah, perabotan rumah tangga yangmewah, mobil, dan lain-lain. Denganmelihat pelacur lain yang berhasil makadiikuti pelacur lain untuk lebih banyakmenghasilkan uang bahkan diikuti olehperempuan lain yang tertarik menjadipelacur. Hal ini sesuai dengan teori belajarsosial atau modelling yang dikemukakanoleh Bandura.
34
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 25-35
B. Rekomendasi
1. Dibutuhkan penanganan yang terpadudan melibatkan antara pemerintah, tokohmasyarakat dan ulama baik dari daerahsetempat maupun bantuan pihak-pihaklain yang terkait untuk menekan tidakbertambah suburnya praktek pelacuran didaerah tersebut. Usaha demikian dapatdimulai dengan mencoba mengubahpersepsi masyarakat akan pelacuran itusendiri yang memang jelas-jelasbertentangan dengan norma-norma susiladan keagamaan dan tidak memberidukungan terhadap apa yang merekalakukan. Bahkan bukan saja bertentangantetapi apabila dilihat dari sudutpendidikan, sosial, kesehatan, kewanitaandan perikemanusiaan, pelacuranmerupakan perilaku yang merusak moralanak-anak yang dalam tahap belajar,juga penyakit sosial yang dapatmenimbulkan berbagai penyakit seksual,menghina kewanitaan dan merendahkan
martabat manusia. Kesadaran akansemua ini perlu ditanamkan padamasyarakat setempat, walaupun akanmemakan waktu yang cukup panjang.
2. Dengan adanya otonomi daerah, baikaparat birokrasi di tingkat pusat maupunpropinsi tidak perlu lagi mempunyai obsesiuntuk menyusun suatu model program atauproyek pembangunan kesejahteraan sosialberskala nasional padahal untukkeperluan lokal. Untuk itu, perlupembentukan pola pikir baru yaitu “ThinkNationally, Act Lokally”, artinya aparatbirokrasi pusat hanya cukup membuatkonsep pembangunan makro sebagairambu nasional, sementara aparatbirokrasi di daerah bersama-samadengan dan/atau masyarakat setempatmenyiapkan model proyek lokal yangsesuai dengan kondisi setempat tetapitetap mengacu kepada kepentingannasional.
DAFTAR PUSTAKA
Alam, AS. 1984. Pelacuran dan Pemerasan. Bandung; Alumni.
Azwar, Saifuddin. 1998. Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta; Pustaka Pelajar. Edisike 2, cetakan III.
Denzin dan Lincoln. 1994. Handbook of Qualitative Research. Thousands Oaks, Sage Publication.
Departemen Sosial RI. 1999. Menuju masyarakat yang berketahanan sosial, pelajaran dari krisis. Jakarta.
Hull, Terrence H; Sulistyaningsih, Endang dan Jones, Gavin W. 1997. Pelacuran di Indonesia. Jakarta;Pustaka Sinar Harapan bekerjasama dengan Ford Foundation.
Kartono, Kartini. 1981. Patologi Sosial. Jakarta; Rajawali.
Sarwono, Sarlito Wirawan. 1995. Teori-teori Psikologi Sosial. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
Siregar, Ashadi; Purnomo, Tjahjo. 1985. Dolly, Membedah dunia pelacuran Surabaya. Jakarta; GrafitiPress.
Siswono, Soejono Dirjo. 1977. Pelacuran ditinjau dari segi hukum dan kenyataan dalam masyarakat.Bandung; PT. Karya Nusantara.
BIODATA PENULIS :
Irmayani, peneliti pada Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Pendidikandan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI. Alumni dari pasca sarjana UniversitasGadjah Mada Yogyakarta dengan Program Studi Psikologi Sosial.
35
Pembentukan Perilaku Pelacuran Berlatar Tradisi di Kab. Pati dan Jepara (Irmayani)
KONDISI SOSIAL PEKERJA ANAK(Assesment Tentang Pekerja Anak di Pesisir Pantai
Cumpat dan Nambangan, Bulak Banteng Kota Surabaya)
Yanuar Farida Wismayanti
ABSTRAK
Kondisi sosial pekerja anak merupakan penelitian kasus di Pesisir Pantai Cumpat dan Nambangan,Bulak Banteng Kota Surabaya yang bertujuan untuk menggali informasi tentang permasalahan sosialpekerja anak. Hasil analisis deskriptif dari assesment yang dilakukan terungkap bahwa faktor ekonomi danlingkungan sosial anak merupakan faktor yang berpengaruh besar terhadap anak sebagai pekerja. Dampakyang paling berpengaruh dari aktivitas anak tersebut adalah putus sekolah. Dalam kerangka mencegahsemakin besarnya populasi pekerja anak, maka diperlukan upaya pelayanan yang menyeluruh, simultandari berbagai pihak yang mempunyai komitmen terhadap anak.
I . PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Permasalahan sosial anak merupakanfenomena yang telah menjadi isu, dan gerakanglobal yang bersifat kemanusiaan (humanity).Kondisi ini tercermin dari perhatian bangsa-bangsa di dunia untuk memberikan per-lindungan dari perilaku diskriminasi daneksploitasi. Menurut perkiraan ILO, sekitar 250juta anak berusia antara 5 sampai 14 tahunambil bagian dalam aktivitas ekonomi dinegara-negara berkembang. Anak yangbekerja purna waktu sebanyak 120 juta.Selebihnya adalah anak yang bekerja tetapijuga bersekolah atau melakukan kegiatan nonekonomis. Secara absolut, Asia merupakanwilayah yang memiliki jumlah pekerja anaktertinggi di dunia, yaitu 61 % di Asia, sedangkansisanya 32 % di Afrika dan 7% di Amerika Latin.
Menurut data Badan Pusat Statistik padatahun 1999 diperkirakan 7% atau 1.400.000anak Indonesia usia 10-14 tahun bekerja. Datalain yang juga penting untuk dipelajari adalahdata dari Departemen Pendidikan Nasionalyang memperkirakan bahwa antara tahun 1995dan 1999 terdapat 11,7 juta anak yang putussekolah berusia 7 sampai 15 tahun. ILO/IPECmemperkirakan bahwa sekitar 6-8 juta anakusia 5 sampai 14 tahun tidak bersekolah,adalah suatu angka yang lebih realistis. Akanlebih relevan lagi bila mengacu pada data anakmuda berusia 15-17 tahun. Menurut laporan
resmi Badan Pusat Statistik, 26 % atau3.400.000 anak muda dari anak muda padakelompok usia tersebut secara ekonomi terlibat,sedangkan 55% masih bersekolah. Sebanyak2.560.634 anak berusia 10 - 17 tahun tengahbekerja di berbagai sektor kegiatan, jumlahtersebut mencapai tujuh persen dari totalangkatan kerja di Indonesia.
Maraknya pekerja anak di Indonesia mini-mal terdapat dua aspek yang berpengaruhbesar. Pertama, meningkatnya angkakemiskinan terlebih lagi semenjak krisis. Tuntutanbiaya hidup, biaya pendidikan anak, dan lainlain semakin besar. Menurut Gunawan danSugiyanto (2005), salah satu strategi untukmengatasi masalah ekonomi keluarga adalahpemanfaatan sumber daya manusia (anggotakeluarga yang ada). Pandangan inimengisyaratkan, bahwa anak merupakan salahsatu aset untuk mengatasi masalah ekonomikeluarga. Akibatnya tidak ada lagi pilihan bagianak, mereka harus bekerja untuk menambahpenghasilan keluarga. Kedua, kurangnyapengawasan terhadap kecenderunganpengusaha menggunakan tenaga kerja anak.Salah satu alasannya adalah pekerja anakdapat dibayar dengan upah yang lebih rendahdibandingkan dengan orang dewasa. MenurutDirektur Eksekutif Organisasi Buruh Internasional(ILO) untuk Standar, Prinsip dan Hak Dasardi Tempat Kerja, Kari Tapiola saat jumpapers bersama Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi (Mennakertrans) Fahmi Idris,(Kompas, 19 April 2005), bahwa Keterlibatan
36
anak di bawah 17 tahun sebagai pekerja dipicubanyak faktor. Salah satunya adalah kemiskinanyang diderita orangtua atau keluarga anak-anak tersebut. Oleh karena itu, pemberdayaanekonomi keluarga menjadi perhatian seriusuntuk dibenahi.
Masalah pekerja anak di Indonesia telahmenjadi perhatian selama bertahun-tahun,walaupun pemerintah baru mulai menanganiisu ini dengan lebih serius setelah krisis ekonomi1997. Melalui UU No. 20/1999 dan UU No.1/2000, pemerintah meratifikasi secara berturut-turut Konvensi ILO No. 138 mengenai usia mini-mum untuk bekerja dan Konvensi No. 182mengenai pelarangan serta tindakan segerauntuk menghapus bentuk-bentuk terburukpekerjaan untuk anak. Namun, meski telah adaUndang-Undang yang melarang anak-anakberusia di bawah 15 tahun untuk bekerja dalamsemua jenis sektor ekonomi, jumlah pekerjaanak masih terus mengalami peningkatan.
Sekalipun kemiskinan merupakanpendorong anak-anak terjun ke dunia kerja,tetapi kenyataan menunjukkan bahwa tidaksemua orang miskin membiarkan anak-anaknyaterjun ke dunia kerja. Berarti, ada faktor-faktorlain, baik faktor sosial, budaya, demografi, ataupsikososial yang ikut mempengaruhi terjunnyaanak-anak ke dunia kerja. Putranto (1995)menyebutkan bahwa masalah kemiskinanbukanlah satu-satunya faktor penyebabtimbulnya masalah pekerja anak. Dengandemikian, ada anggapan bahwa per-masalahan pekerja anak akan hilang dengansendirinya apabila permasalahan kemiskinandapat diatasi, merupakan pandangan yangkeliru. Sedangkan kekuatan ekonomi telahmendorong anak-anak masuk ke dalampekerjaan di lingkungan yang membahayakanmerupakan kekuatan yang paling besar darisemuanya, tetapi adat dan pola sosial yangtelah berakar juga memainkan peranan.
Berbagai bentuk keterlantaran maupuneksploitasi anak dapat berdampak negatif bagitumbuh kembang mereka. Sekalipun berbagaiperaturan telah ditetapkan untuk melindungianak, pada kenyataannya tidak sedikitperlakuan pengusaha atau majikan tanpamempertimbangkan dampak buruknya padaanak, seperti: praktik eksploitasi, penempatananak pada pekerjaan yang tidak sesuai dengankondisi fisiknya, bahkan berbahaya bagi
keselamatan jiwanya. Berdasar dari kondisi diatas, maka permasalahan yang menarik untukdicermati adalah bagaimana kondisi anak-anak yang bekerja tersebut? Jawaban daripertanyaan ini tentunya merupakan informasiyang bermanfaat dalam kerangka per-lindungan anak dari proses marginalisasi, daneksploitasi.
B. Tujuan
1. Teridentifikasi kondisi pekerja anak
2. Teridentifikasinya faktor yang mem-pengaruhi anak menjadi pekerja
3. Teridentifikasinya permasalahan anakyang bekerja
C. Tinjauan Pustaka
Dalam beberapa ketentuan hukum,manusia disebut sebagai anak denganpengukuran/batasan usia. Kondisi ini tercermindari perbedaan batasan usia, menurut KonvensiHak Anak (KHA), maupun UU No 23/2002tentang Perlindungan Anak. Menurut KHA,definisi anak secara umum adalah manusiayang umurnya belum mencapai 18 tahun.Dalam implementasi keputusan KHA tersebut,setiap negara diberikan peluang untukmenentukan berapa usia manusia yangdikategorikan sebagai anak. Dalam KHA (pasal1) disebutkan bahwa “anak berarti setiapmanusia yang berusia di bawah delapan belastahun kecuali berdasarkan undang-undangyang berlaku untuk anak-anak, kedewasaantelah dicapai lebih cepat. Hal yang samajuga dijelaskan dalam Undang-Undang Per-lindungan Anak No 23 tahun 2002, bahwaanak adalah seseorang yang belum berusia 18tahun termasuk anak yang masih dalamkandungan.
Dalam kaitannya dengan pekerja anak,Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakanbahwa pekerja anak adalah anak yang berusia10-14 tahun yang melakukan pekerjaandengan maksud memperoleh pendapatankeuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit1 jam secara kontinyu dalam seminggu yanglalu. Jika pengertian ini dikaitkan denganbatasan usia anak baik dari KHA maupun UUNo.23/2000, maka seorang yang usianyaantara 15-18 dapat dikategorikan bukanpekerja anak. Hal yang lebih penting adalah
37
Kondisi Sosial Pekerja Anak (Yanuar Farida Wismayanti)
kondisi anak pada usia 10-15 tahun tersebut.Kondisi ini dapat dipahami karena anak padausia 15 tahun ke atas telah terbebas dari wajibbelajar (9 tahun). Dalam pengertian yang lebihluas, ILO mendefinisikan pekerja anak adalah:“Children who lost their childhood and future,prematurely leading adult lives, working longhours for low wages under conditions damagingto their health and their physical and mental de-velopment.”
Dari kondisi semacam ini, makapertanyaannya adalah bagaimana anak-anaktersebut dapat memperoleh hak-haknya sesuaidengan yang termaktub di dalam KHA, yakni:
1. Kelangsungan hidup, diantaranya : a)pemenuhan kebutuhan dasar, berupasandang, pangan , perumahan dan airbersih, b) kemampuan untuk memeliharakesehatan diri sendiri dan lingkungan danc) akses terhadap pelayanan kesehatanyang terbatas.
2. Tumbuh kembang, diantaranya : a) aksesmemperoleh pendidikan, pelatihan dankesempatan untuk bermain danbersosialisasi, b) memiliki mental yangcenderung labil, sehingga mudahterpengaruh terhadap perilakumenyimpang, c) lingkungan yang rentanterhadap tumbuh kembang baik secarafisik, sosial, mental dan spiritual anak.
3. Perlindungan, diantaranya : a) ketiadaanidentitas, seperti akta kelahiran,menyebabkan anak rawan terhadapdiskriminasi dan eksploitasi, b) rawanterhadap perlakuan salah dan berkonflikdengan hukum, c) lemahnya upayaperlindungan terhadap anak yangberkonflik dengan hukum di tempat kerjasektor informal.
4. Partisipasi diantaranya: a) penghargaanterhadap pendapat anak, b) perhatiandan pertimbangan pandangan anakdalam setiap proses pengambilankeputusan pada setiap kegiatanpelayanan sosial, c) kesempatan untukmenyalurkan aspirasi baik di lingkungankeluarga maupun masyarakat, d) wadahuntuk berpartisipasi.
Dalam kondisi normal pemenuhan hakanak dimaksud merupakan tanggung jawaborang-tuanya. Namun pada kondisi tertentuatau karena kurangnya pengetahuan, kelalaian,tidak semua orang tua dapat merealisasikankebutuhan anaknya secara penuh. Sebagaiilustrasi, Asra (1993) mengemukaan bahwa35 % orang tua akan mengalami penurunanpendapatan keluarganya jika anak merekaberhenti bekerja. Sedangkan Imawam dkk.(1999) menemukan 23,5 % pendapatan anak-anak yang bekerja diberikan untuk orangtuanya. Hal ini disebabkan anak-anakmembutuhkan pekerjaan justru karena keadaanekonomi keluarganya yang miskin.
Pada kasus ini, pekerja anak dapatdipandang sebagai salah satu bentukeksploitasi. Kompensasi yang diberikan kepadaanak, atas pekerjaannya sangat kecil. terlebihlagi jika pekerjaan yang diberikan tanpapertimbangan bagi perkembangankepribadian mereka, keamanannya, kesehatan,dan prospek masa depan. Ilustrasi di atasmengindikasikan adanya ketidak-mampuankeluarga dalam menjalankan fungsi ekonomidan pendidikan, pertumbuhan danperkembangan anak. Akibat lanjut dari kondisiini adalah rendahnya kemampuan (daya saing)anak dikemudian hari yang semakin menuntutkualitas anak. dalam konteks ini, kemiskinankeluarga dan pekerja anak dapat dipahamisebagai mata rantai yang saling berkaitan.
Jika dipahami bahwa pekerja anak dankemiskinan keluarga sebagai mata rantai yangsaling berkaitan, maka permasalahan pekerjaanak pada dasarnya merupakan fenomenayang selalu dapat dijumpai di negara miskindan negara yang sedang berkembang.Berbagai ketentuan hukum untuk perlindungananak tersusun, baik di tingkat dunia (ILO No182 mengenai Pelarangan dan Tindakansegera untuk Penghapusan Bentuk-BentukPekerjaan Terburuk untuk Anak), maupunnasional (UU No. 23 tahun 2002, tentangPerlindungan Anak). Program-program untukmengatasi masalah kemiskinan keluarga(seperti: penanganan masalah kemiskinan,pengentasan kemiskinan, pemberdayaankeluarga dan lain-lain)telah banyak dilakukan.Namun, jumlah pekerja anak tidak menunjukkanadanya penurunan.
38
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 36-46
Persoalan yang menarik untuk dicermatiadalah apakah pekerjaan tersebut mem-bahayakan anak bagi pertumbuhan danperkembangan anak serta masa depan anak.Dalam buku Laporan Kunjungan ke India;Pekerja Anak di Indonesia (2003;10) ILOmembedakan antara pekerjaan ringan (lightwork) dengan pekerjaan berbahaya (hazardouswork). Pekerjaan ringan adalah pekerjaan yangtidak berbahaya bagi kesehatan danperkembangan anak, tidak mengganggujadwal sekolah, jam kerja tidak panjang.Sedangkan pekerjaan berbahaya adalahpekerjaan yang berdasar sifat atau kondisinyadapat membahayakan kesehatan, keselamatandan moral anak. Perbedaan jenis pekerjaantersebut mengisyaratkan adanya jenis-jenispekerjaan yang boleh dilakukan/ditolerir olehanak. Jenis pekerjaan dimaksud adalahpekerjaan yang tidak mengganggu atau tanpamengurangi hak-hak anak.
Berdasarkan uraian di atas dapatdikemukakan, bahwa dalam konteks pekerjaanak, ada beberapa faktor penyebab anakbekerja. Di samping itu juga berbagai resikoyang dialami oleh pekerja anak menyebabkananak-anak berada dalam kondisi yangtermarginalkan, serta mengalami pelanggaranatas hak-hak anak. Oleh karena itu dalamkerangka memahami kondisi sosial pekerjaanak, paling tidak terdapat dua hal pentingberkaitan dengan pemenuhan hak anak, yaitu:
1. Kondisi umum pekerja anak berkaitandengan pemenuhan kebutuhan dasar,dilihat dari aspek karakteristik pekerja anakdan penyebab anak bekerja.
2. Permasalahan dalam pemenuhan hakanak, tinjauan tentang permasalahanterhadap pemenuhan hak anak ini dapatdilihat dari aspek diantaranya pendidikan,kesehatan, rekreasi/waktu bermain,bahaya/resiko anak yang bekerja, sertapandangan masyarakat terhadap pekerjaanak.
D. Metodologi Penelitian
Kondisi sosial pekerja anak merupakanpenelitian kasus di pesisir pantai Nambangandan Cumpat, Kelurahan Kedung Cowek,Kecamatan Bulak Banteng Kota Surabaya.Informasi tentang anak yang bekerja akan
dihimpun dari 20 anak yang bekerja,wawancara mendalam terhadap beberapainforman diantaranya orang tua mereka, tokohagama, tokoh pemuda setempat, pihakkelurahan, juragan ikan, juga staf LSM di tingkatlokal kecamatan dan kotamadya. Tehnikpengumpulan data yang digunakan adalah :1) Observasi, yaitu pengamatan secaralangsung terhadap kegiatan anak-anak yangdipekerjakan, 2) Wawancara mendalamkepada anak yang bekerja, 3) Focussed GroupDiscussion (Diskusi Kelompok Terfokus) denganstakeholder, baik itu orang tua, kelompok anak-anak dan remaja, 4) Studi dokumentasi. Datayang terhimpun dianalisis secara deskriptif.
I I . HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Tidak ada data tertulis dan cerita detailyang bisa menggambarkan sejarahNambangan. Ada dua versi tentang asal kataNambangan, versi pertama Nambanganberasal dari kata “nambang”, yang artinyaberlayar menggunakan sampan. Hal iniberkaitan dengan cerita bencana banjir yangterjadi di wilayah Gresik, daerah pesisir yangberada di sebelah barat Surabaya. Orang-or-ang mengungsi dengan mengendara perahusampan menelusuri laut utara dan akhirnyaterdampar di sebuah tempat yang aman daribencana banjir. Versi kedua, Nambanganberasal dari kata “nambang” yang artinyamenambang. Awalnya orang-orang dari Gresikdatang ke tempat itu untuk menambang perak,makanya kemudian tempat itu bernamaNambangan Perak. Tempat itulah yangkemudian menjadi cikal bakal KampungNambangan Perak yang dikenal saat ini. Bisajadi orang-orang Gresik jaman dahulu adalahnenek moyang masyarakat Nambangan, tetapimasyarakat Nambangan saat ini akanmengatakan dirinya “asli” Nambangan karenamereka lahir dan hidup di wilayah tersebut.
Nambangan termasuk wilayah kelurahanKedung Cowek, Kecamatan Bulak Banteng KotaSurabaya. Yang secara geografis daerah iniberbatasan dengan Tambak Wedi (Utara),Cumpat (Selatan), Selat Madura (Timur) danKedinding Lor (Barat). Tata ruang kampungNelayan ini sekilas tampak sesak karena rumah-rumah yang sangat berdekatan. Selain itu,
39
Kondisi Sosial Pekerja Anak (Yanuar Farida Wismayanti)
hampir semua warga Nambangan tidakmemiliki WC. Mereka hanya membangunkamar mandi, sementara untuk aktifitas buangair besar, mereka biasa melakukannya di alamterbuka. Biasanya di tepi pantai atau di rumput-rumput yang tumbuh di lahan kosong sebelahbarat perkampungan. Semrawutnya kampungini juga terlihat dari sampah yang tidak dikeloladengan baik. Banyak sampah dibuangsembarangan dan tercecer dimana-mana.Ketika musim hujan, bau menyengat takterelakkan lagi karena system drainase yangtidak memadai. Kondisi fisik Nambangan tentusaja mengalami perkembangan dari waktu kewaktu. Perluasan pemukiman penduduk,jalannya aspal, masuknya listrik dan PDAMyang saat ini dinikmati warganya adalah contohsukses pembangunan yang dicanangkanpemerintah.
Sedangkan mata pencaharian masyarakatNambangan sebagian besar adalah Nelayan,bisa dikatakan 90%, dan 10% sisanya adalahPNS, pedagang dan Wiraswasta. Untuk PNSbiasanya adalah guru dan perangkatpemerintah, untuk pedagang biasanya adalahpedagang kelontong, penjual nasi dan warung(warung kopi) sedangkan wiraswasta adalahpengusaha gypsum, tukang becak danpengepul ikan.
Ada dua macam nelayan di Nambangan,yaitu nelayan pencari kerang dan nelayanpemasang perangkap ikan. Nelayan pencarikerang sehari-harinya menyelam ke dasar laut,dalamnya sekitar 7-9 meter, untuk pernafasansi penyelam di bantu dengan udara darikompresor yang diletakkan di atas perahu.Dalam mencari kerang waktu yang dibutuhkanbiasanya 1 sampai 2 jam, lokasi mencarikerang berpindah-pindah dan tidak mengenalmusim, kadang-kadang jika kerang di sekitarNambangan telah habis, maka nelayan bisamencapai daerah perairan Juanda atauMadura untuk mencari lokasi yang masihbanyak kerangnya.Sedangkan nelayanpemasang ikan, biasanya menangkap ikan dilokasi yang sudah ditetapkan, yang ditandaidengan memasang turus. Turus terbuat daribatang pohon kelapa sepanjang 9 sampai 12meter yang ditancapkan tegak lurus ke dasarlaut. Turus ini berfungsi untuk menambatkanperahu dan juga untuk mengikatkan jaring yangdipasang sebagai perangkap ikan. Nelayanpemasang perangkap ikan ini biasanya
memasang jaring sekitar pukul 24.00 sampaipukul 03.00 dini hari, baru paginya sekitar pukul07.00 sampai pukul 10.00 mereka mengambiltangkapan jaringannya.
Berdasarkan data kependudukan diKelurahan Kedungcowek menujukkan jumlahpenduduk usia 0-4 tahun adalah 471, laki-lakiberjumlah 240 dan perempuan 231. Pendudukusia 5-6 tahun 180, laki-laki berjumlah 98 danperempuan 82. Penduduk usia 7-13 tahunadalah 621, laki-laki berjumlah 324 danperempuan berjumlah 291. Penduduk usia 14-17 tahun adalah 340, laki-laki berjumlah 172dan perempuan 168.
Tentang kondisi pendidikan anak-anak,taraf pendidikan di Nambangan lebih tinggidibandingkan dengan di Cumpat. DiNambangan yang sampai lulus PerguruanTinggi cukup banyak, sedangkan di Cumpatkebanyakan setelah lulus SD, SMP atau SMAlangsung bekerja di laut. Keenganan merekauntuk meneruskan pendidikan yaitu disebabkanoleh kesadaran masyarakat yang kurangterhadap pentingnya pendidikan. Di sampingitu juga kurangnya motivasi anak-anak untukmelanjutkan pendidikan.
B. Kondisi Anak
Berdasar data yang terhimpun dari 20pekerja anak, maka karakteristik pekerja anakdapat ditinjau dari beberapa aspek. Gambarantentang pekerja anak tersebut dapatdikemukakan sebagai berikut: Ditinjau dari jeniskelamin, jumlah anak laki-laki 5 orang (25%)dan perempuan 15 orang (75%). Sedangkanusia responden berkisar antara 9 tahun sampaidengan 14 tahun, terdiri dari usia 9-11 tahunsebanyak 8 orang (40%) dan usia 12-14 tahunsebanyak 12 orang (60%). Data tersebut,menunjukkan bahwa usia pekerja anaksebagian besar antara 9-12 tahun. di manapada usia tersebut anak seharusnyamendapatkan pendidikan dasar di sekolah.anak-anak tersebut masih dalam kondisi wajibbelajar 9 tahun. Kondisi ini dapat berpengaruhnegatif terhadap pendidikan anak atau bahkanterabaikan.
Dilihat dari pendidikannya, sebagianbesar responden masih sekolah SD sebanyak11 orang (55%), SMP sebanyak 3 orang (15%)dan 6 orang (30%) tidak melanjutkan sekolahatau lulus SD saja. Putus sekolah nampaknya
40
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 36-46
bukan masalah bagi mereka, karena pendidikanbelum menjadi prioritas. Keadaan inimengindikasikan kurangnya kesadaranmasyarakat terhadap pendidikan anak-anaknya. Pendidikan masyarakat di lokasipenelitian ini adalah menengah ke bawah,bahkan banyak diantaranya adalah anak-anak putus sekolah. Kurangnya kesadaranmasyarakat terhadap pendidikan tersebut jugatercermin dari pandangan masyarakat, bahwadengan hasil laut saja sudah bisa hidup,mengapa harus sekolah tinggi-tinggi? Kondisiini diperburuk dengan sulitnya akses untukpendidikan dan ekonomi keluarga relatif statis.Jika ada anak yang ingin melanjutkanpendidikan, maka ia harus sekolah di luardaerah tersebut. Biaya pendidikan menjadilebih besar, sementara itu keluarga hanyamenggantungkan hasil dari laut denganpengelolaan yang sangat sederhana. Orangtuaenggan untuk menyekolahkan anak karenatuntutan biaya yang relatif tinggi.
Dalam kehidupan sehari-hari, anak tinggaldengan keluarga di rumah yang ukurannyarelatif kecil, sedangkan jumlah anggotakeluarga relatif besar. Rata-rata dalam saturumah terdapat sekitar 5-10 orang. Merekaterdiri dari saudara sepupu, paman (guk), bibi,kakak laki-laki (cacak), kakak perempuan (ning),adik, nenek, ipar, ayah (abah) dan ibu (emak/ummi). Dari segi kesehatan, kondisi ini relatifkurang memenuhi syarat. Namun untuk interaksisosial antara anggota masyarakat menjadi lebihbesar. Interaksi sosial ini dapat menjadi salahsatu kekuatan untuk mengatasi masalah,misalnya untuk memenuhi kebutuhan makannya,biasanya selain makan di rumah mereka jugameminta makan ke rumah nenek atau di rumahsepupunya.
C. Penyebab anak bekerja
Jenis pekerjaan yang dilakukan anak-anakdi pesisir, antara lain: mencari lorjuk (karanglorjuk), mengupas kerang, mbelek ikan(membelah ikan) dan mencari ikan di laut. Jenispekerjaan anak pada dasarnya mempunyaiketerkaitan dengan jenis pekerjaan baik yangdilakukan oleh orang tua maupun teman-temannya. Jenis pekerjaan anak yang adaketerkaitannya dengan pekerjaan orang tuaadalah mbelek ikan dan mencari ikan di laut.Anak-anak melakukan pekerjaan tersebut lebihbanyak dilandasi oleh faktor ekonomi. Mereka
membantu orang tua untuk meningkatkanpendapatan keluarga, bahkan ada beberapaanak yang terpaksa bekerja, karena harusmenggantikan peran sebagai kepala keluargasetelah bapaknya meninggal dunia. Sejak kecilanak-anak tersebut telah disosialisasi pekerjaanorang tua, mulai dari mengenalkan jenispekerjaannya sampai dengan apa yang harusdikerjakan oleh anak, sehingga anak-anaktersebut telah terbiasa dengan pekerjaan itu.Sebagai ilustrasi, ibu yang bekerja sebagaipembelek ikan sambil mengasuh anak. Disadariataupun tidak jenis pekerjaan ini akantersosialisasi pada anak. Ketika itu anak mulaibermain dan akrab dengan jenis pekerjaanorang tuanya dan mulai ikut-ikutan. Pada saatsudah mulai bisa produksi (dapat menghasilkanseperti orang tuanya), maka saat itulah anakmulai terlibat dengan pekerjaan orangtuanya.Jenis pekerjaan ini banyak dilakukan oleh anak-anak wanita, sedangkan anak yang telah mulairemaja mulai dikenalkan dengan pekerjaanorang tua (ayah) sebagai nelayan.
Aspek lain yang mendorong anak bekerjaadalah faktor lingkungan pergaulan anak (peergroup). Pada awalnya anak hanya ikut-ikutantemannya mencari kerang lorjuk di pesisir pantai.Lama-kelamaan aktivitas mereka menjadi“keterusan” dan menjadi pekerjaan mereka.Mereka mendapatkan uang dari penjualan hasillorjuk yang mereka peroleh. Uang yangdiperoleh digunakan untuk jajan dan sebagianlagi ditabung atau diberikan kepada orang tua.Dari beberapa responden juga ada yangmenyampaikan bahwa mereka bekerja mencarikerang lorjuk sekedar untuk mengisi waktu luangsaja. Daripada nganggur di rumah, sekalianitung-itung dapat uang untuk tambahan jajanatau untuk kepentingan yang lain. Sekitar jamtiga sore, saat laut pun mulai surut, anak-anakmembawa sebuah timba, pakan (bahan yangterbuat dari campuran cabe, kapur dandeterjen), Tubo (kayu yang terbuat dari bambuberbentuk kecil), Rokcarok (semacam bendayang terbuat dari seng dan diberi gagang kayu)dan pare’an (kayu yang berukuran ± 10 x 20cm) dari rumahnya menuju ke laut. Anak-anakitu bergegas menuju ke laut bersama denganteman-temannya, dan menuju ke tengah lautyang memang dari tadi sudah surut. Merekaberniat mencari kerang lorjuk di tengah laut,dan sesampainya di tengah laut mereka melihatsekeliling untuk melihat dimana yang banyaklorjuknya.
41
Kondisi Sosial Pekerja Anak (Yanuar Farida Wismayanti)
Pekerjaan mbelek ikan, mencari lorjuk dansebagainya merupakan kegiatan yang telahdilakukan oleh anak-anak secara rutin. Merekamerupakan tenaga terampil layaknya orangdewasa. mbelek ikan dan mengupas kerangbanyak dilakukan oleh anak-anak perempuan.Mereka melakukan pekerjaan dengankesabaran, cermat dan secara lebih teliti. Padahari-hari tertentu (hari libur sekolah) anak laki-laki lebih senang melakukan pekerjaan di tepilaut. Ketika air laut surut, anak anak bergegaske pantai.Ada beberapa ikan yang biasanyamereka cari yaitu lorjuk, glomo, dan kerangthotok.
D. Tinjauan Terhadap Jenis PekerjaanAnak
Tinjauan tentang jenis pekerjaan anakakan dilihat dari aspek resiko terhadap anakatas pekerjaannya. apakah pekerjaan yangdilakukan anak tersebut beresiko (berat danmembahayakan) karena fisiknya yang masihrelatif lemah, berpengaruh buruk terhadapmasa depan anak, atau pekerjaan tersebutmempunyai unsur positif bagi perkembangananak (sebagai wahana pendidikan dan latihanbagi anak). Pekerjaan anak dipandang beratjika sifat atau kondisinya dapat membahayakankesehatan, keselamatan dan moral anak.Pekerjaan dapat dipandang mempunyai unsurpositif untuk pengembangan anak jikapekerjaan tersebut tidak berbahaya bagikesehatan dan perkembangan anak, tidakmengganggu jadwal sekolah, jam kerja tidakpanjang.
Nachrowi (1996) menyebutkan bahwafaktor-faktor yang mempengaruhi adanyapekerja anak perlu dilihat dalam perspektif yanglengkap, yaitu dengan melihat dari dua sisi yangberbeda: sisi penawaran dan sisi permintaan.Sekalipun masyarakat menyediakan tenagakerja anak, tetapi jika tidak ada perusahaanyang mempekerjakannya, sudah pasti pekerjaanak tidak muncul. Demikian pula sebaliknya,bila permintaan terhadap pekerja anak tinggitetapi masyarakat tidak menyediakan makapekerja anak juga tidak akan muncul. Dalamhal ini tentunya ada sebuah kondisi yangberlaku, dimana tingginya supply terhadappekerja anak, juga didorong faktor demandterhadap pekerja anak yang cukup menjanjikan.
Dari observasi dan wawancara yangdilakukan di lokasi penelitian ini dapat
diinventarisasi beberapa jenis pekerjaan yangdapat dikelompokkan dalam kategori relatifberat (berbahaya), dan kondusif untukperkembangan anak. Pekerjaan yang relatiftidak berbahaya adalah jenis pekerjaan yanglebih banyak dilakukan di darat (seperti mbelekikan, mengupas kerang dan lain-lain),sedangkan pekerjaan yang relatif beresikoadalah pekerjaan yang dilakukan di tepi lautdan di tengah laut.
Sebagai ilustrasi, pekerjaan yang dilakukanoleh anak-anak di darat seperti mbelek ikan,membersihkan bulu ayam dan gragomerupakan pekerjaan yang relatif aman untukanak-anak. Lia membantu emaknya membelah(mbelek) ikan di rumah Wak Joi sebagai salahsatu pengusaha (juragan) ikan di Nambangan.Sepintas memang terkesan bahwa pekerjaanyang dilakukan anak tersebut merupakan salahsatu bentuk eksploitasi. Waktu bermain anakberkurang ketika mereka harus melakukanpekerjaan setelah pulang sekolah. Selamapekerjaan yang dilakukan tidak menggangguatau mengurangi hak-haknya untuk masadepannya, maka pekerjaan itu belum dapatdikategorikan sebagai eksploitasi. Di lingkunganini, Lia mendapat pengalaman/keterampilanyang didapat diluar pendidikan formal. TanganLia sudah terampil melakukan pekerjaan mbelekikan, terampil membersihkan bulu ayam dangrago, karena sejak umur 7 tahun telah terbiasamelakukan pekerjaan ini. Keterampilan yangdiajarkan oleh emaknya dapat menjadi bekalbagi anak. Jenis pekerjaan ini membutuhkanketelitian, ketekunan sehingga lebih banyakdilakukan oleh pekerja anak wanita. Adapunjenis pekerjaaan yang dilakukan oleh anak laki-laki lebih banyak dilakukan dipesisir pantai.Mereka melakukan aktivitas pekerjaan ini setelahpulang sekolah pada saat air laut sedang surut.Bagi anak-anak, laut merupakan lahanpekerjaannya dan sekaligus merupakan tempatbermain.
Aktivitas pekerjaan Lia dan anak anakyang lain sepanjang tidak menggangguperkembangannya, kesehatannya, dankeselamatan hidupnya, maka pekerjaan inimasih dapat ditolerir. Bahkan beberapa jenispekerjaan yang dilakukan oleh anak tersebutmasih dapat dipahami sebagai salah satubentuk hiburan dan latihan bagi kemandiriananak (lifeskill). Dipandang sebagai hiburansepanjang anak melakukan pekerjaan tersebut
42
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 36-46
dengan penuh suka cita. Mereka melakukanpekerjaan dan sekaligus bermain. Anak-anakyang polos dan kehidupannya yang seolahtanpa beban karena dunia mereka adalahbermain. Permainan anak pada kasus ini tidakhanya sebatas pada permainan yang dipahamioleh masyarakat pada umumnya yang perludilengkapi dengan peralatan permainan sepertibola, bekel, boneka dan lain-lain. Dalamkeseharian anak biasa bermain setelah pulangsekolah hingga sebelum ashar. Anak-anakbermain dengan kelompok teman sebaya danjenis kelamin yang sama. Di pesisir anak laki-laki biasa bermain sepak bola, mandi di laut(anak-anak menyebutnya dengan jeguran) danbersepeda. Permainan ini mereka pandangsebagai sesuatu yang sangat menyenangkandan mereka sangat menikmati.
Meskipun aktivitas anak yang melakukanpekerjaan tersebut, tidak cukup menggangguaktivitas utamanya. Namun demikian perludipertimbangkan kenyamanan bagi anak-anakdalam beraktivitas. Untuk itu pemenuhan akankebutuhan sosial ini adalah hal yang sangatpenting. Diantaranya kebutuhan untuk diterimasebagai anggota kelompok atau menerimaorang lain sebagai anggota kelompok, bermainbersama, kepedulian dan tanggung jawabsosial terhadap temannya. Melalui pemenuhankebutuhan tersebut akan memberikan dampakyang positif bagi tumbuh kembang anak.
Dari segi pendidikan dan pengembangandiri, aktivitas pekerjaan yang dilakukan olehanak merupakan salah satu bentuk pengenalantentang lingkungan dan realitas yang dialamioleh orang tua terhadap anak. Anak-anakperempuan menjadi tenaga terampil dancekatan, anak laki-laki lebih mengenal alamdan lingkungannya. informasi yang mereka milikiselama ini tentunya dapat menjadi bekal anakyang bermanfaat besar ketika anak-anaktersebut menginjak dewasa.
Hal yang menarik dan perlu dicermatiadalah apakah pekerjaan yang mereka lakukanmenuntut tanggung jawab yang tinggi (sepertilayaknya orang dewasa), sehingga dapatmengganggu aktivitas belajar mereka? Jikayang terjadi adalah tuntutan tanggung jawabdari orang atau lembaga yang mempekerjakanmaka kasus ini dapat dikonotasikan sebagaisalah satu bentuk eksploitasi.
Umumnya orang-orang dewasa diwilayah Cumpat dan Nambangan memandangpekerja anak di pesisir pantai sebagai sesuatuyang tidak bermasalah. Anak-anak yangbekerja tersebut sekedar membantu orangtuanya apabila tidak ada pekerjaan yangdilakukan di rumah atau kegiatan pengajiandan sekolah. Walaupun beberapa orang tuaberpikir bahwa kondisi sekarang lebih baikdibandingkan waktu mereka masih muda,terlihat dengan kesempatan mereka untukmengenyam bangku pendidikan dan tehnologiinformasi (televisi, radio dll) dirasakan lebihmudah diperoleh oleh anak-anak sekarang.Menurut pengakuan orang tua anak-anaktersebut, “sebenarnya mereka juga kasihandengan anaknya yang masih kecil tapi sudahbekerja, tapi karena ayahnya sudah meninggalmau nggak mau harus membantu keluarga”,tegas Mak Julaikho. Berbagai pandanganmasyarakat terhadap pekerja anak, merupakansebuah peluang yang perlu dibangun untukkepentingan terbaik bagi anak. Pada dasarnya,sebagaian besar masyarakat menyadari bahwatidak seharusnya anak-anak bekerja.
Pada kasus pekerjaan yang dilakukan Liaketika liburan sekolah. Lia melakukan pekerjaansejak subuh hingga selesai atau Lia bolehmeninggalkan pekerjaan ketika sudah merasalelah. Sebagai imbalan hasil jerih payahnya Liadiberi Rp. 1.000,- oleh ibunya. Pada kasus initidak hanya terjadi pada Lia, atau kasus lainnyayakni anak-anak yang diajak oleh orang tuanyamenangkap ikan di laut. Mungkin Lia atau anak-anak mempunyai kondisi yang sama tidak bisamenikmati waktu bermainnya. Melihat kondisikesehatan dan keselamatan kerja para pekerjaanak, maka pelayanan kesehatan dankeselamatan kerja sangat penting bagi anak-anak. Hal ini bertujuan untuk memperolehstandar kehidupan yang layak agar merekaberkembang fisik, mental, spiritual, moralmaupun sosial dengan baik, termasuk hak anakuntuk memperoleh pelayanan kesehatan danjaminan sosial.
Pada kasus yang dialami oleh anak laki-laki yang bekerja sekaligus bermain di laut,anak tidak begitu menyadari adanya bahaya.Gelombang air pasang yang sewaktu-waktudapat datang, ikan ganas, atau bahaya lainyang dapat ditimbulkan oleh pekerjaan orangdewasa. Sebagai ilustrasi, penggunaan alat
43
Kondisi Sosial Pekerja Anak (Yanuar Farida Wismayanti)
selam kompresor oleh nelayan pada saatmenangkap ikan. Keteledoran, kelalaian dalampenggunaan alat atau gelombang air dapatmempengaruhi fungsi alat yang berakibat fa-tal bagi penggunanya. Mereka yang meninggalbiasanya disebabkan karena terlilit dan atautersumbatnya selang udara yang dihubungkandengan kompresor. Penyelam tidak bisamendapatkan udara untuk pernafasan dariselang tersebut. Resiko lainnya adalah terserangpenyakit pernafasan, biasanya merekaterserang penyakit paru-paru yang disebabkanoleh karat atau debu dari kompresor. Kasus inipernah dialami oleh nelayan pencari kerangyang sakit paru-paru. Besar kemungkinannya,bahwa kejadian ini dapat dialami oleh anakyang ikut melakukan pekerjaan orang tuanya.Mungkin dampaknya tidak secara langsungdirasakan, namun akan berpengaruh terhadaptingkat kesehatan mereka. Dampak pekerjaananak-anak tersebut memang tidak secaralangsung dirasakan. Namun demikian kondisiini harus diantisipasi lebih awal. Dengandemikian isu perlindungan terhadap anakmerupakan isu yang paling penting. Salahsatunya adalah melindungi anak-anak daribahaya yang akan membahayakan jiwanya.Karena itu sangat penting memberikanperhatian terhadap kondisi kesehatan dankeselamatan kerja para pekerja anak. Makapelayanan kesehatan dan keselamatan kerjasangat penting bagi anak-anak. Hal inibertujuan untuk memperoleh standar kehidupanyang layak agar mereka berkembang fisik,mental, spiritual, moral maupun sosial denganbaik.
Banyak usaha yang telah dilakukan untukmenghapus pekerja anak melalui model-modelyang disusun oleh akademisi, program kegiatanLSM, bahkan aksi atau kebijakan pemerintah.Usaha pemerintah yang terbaru mempunyaisasaran menghapus bentuk-bentuk terburukpekerjaan untuk anak. Suyanto (2002), seorangpengamat pekerja anak, telah mengidentifikasitiga prioritas dalam menyusun programkegiatan: perlindungan dan pemberdayaanpekerja anak, kesempatan dan akses untukmenerima pendidikan secara maksimum dankompetensi institusional untuk menanganimasalah-masalah pekerja anak
Untuk menghapus bentuk-bentuk terburukpekerjaan pada anak-anak memerlukanberbagai strategi dan pendekatan yang tepat
bagi mereka. Menurut Haryadi dan N. Sukarna(1999), terdapat tiga pendekatan untukmenyelesaikan masalah pekerja anak yaitu ;eliminasi, proteksi, dan pemberdayaan.Masing-masing pendekatan memiliki asumsi,nilai dan pandangan sendiri. Pendekataneliminasi memandang bahwa anak-anak hanyaboleh bermain dan belajar, tidak bekerja.Pandangan ini, walaupun dominan, tidaklahrealistis dan sulit untuk diterapkan karenamengabaikan kenyataan bahwa masalahpekerja anak disebabkan oleh kemiskinanstruktural. Solusi atas masalah pekerja anak tidakhanya dengan mengharuskan merekabersekolah tetapi juga menstrukturisasi ekonomi.Dua pendekatan lainnya memperbolehkananak-anak untuk bekerja karena sebagai indi-vidual anak-anak mempunyai hak ekonomiuntuk bekerja selama ada jaminan bahwamereka diperlakukan dengan baik dan tidakdiabaikan atau dilecehkan. Selanjutnya Suyanto(2002) mengatakan bahwa masalah pekerjaanak tidak dapat diselesaikan hanya denganmenggunakan pendekatan legalistik-formalistikserta tindakan-tindakan yang bersifatmenghukum, melainkan harus disertai denganpendekatan sosial dan budaya yang menyentuhakar permasalahan. Dibutuhkan suatu programintervensi yang komprehensif, sepertipeningkatan kualitas hidup untuk keluarga-keluarga yang hidup dalam kemiskinan,peningkatan kesadaran mengenai hak-hak anakdan komitmen yang disertai langkah-langkahyang konkrit.
I I I. PENUTUP
A. Kesimpulan
Ketika berbicara tentang pekerja anakmemang merupakan suatu kondisi yang cukupsulit untuk memberikan pemahaman tentangbatasan-batasannya. Ada beberapa persoalanyang melatarbelakangi munculnya pekerjaanak, dan kondisinya sangat bervariasi. Banyakkeluarga yang hidupnya pas-pasan sangatdibantu oleh tambahan pemasukan dari anak-anak yang bekerja. Sebagian di antara anak-anak tersebut diminta oleh orang tuanya untukbekerja, namun banyak juga anak-anak yangmemang ingin membantu, terutama bila aksesterhadap pendidikan sangat terbatas danmereka hanya memiliki sedikit kegiatan yangsifatnya untuk mengisi waktu. Melalui
44
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 36-46
perlindungan atas hak-hak anak khususnyaterhadap anak-anak yang bekerja di sektorbekerja memerlukan perhatian yang cukupserius.
Namun yang lebih penting lagi adalahbagaimana mengimplementasikannya,sehingga Upaya Penghapusan Bentuk-BentukPekerjaan Terburuk Untuk Anak tidak sebataskampanye. Perlu adanya kerjasama denganinstansi terkait termasuk masyarakat luas untukmemberikan proteksi dan pemberdayaan yanglebih realistis kepada anak-anak. Untuk itu perlusebuah pendekatan untuk meningkatkankemampuan implementasi dari peraturan KILO182 diantaranya melalui perbaikan pendidikansebagai instrumen untuk menghentikaneksploitasi anak-anak serta kampanye untukmemberikan perlindungan terhadap anak-anakatas hak mereka. Kondisi ini juga harus didukungdengan restrukturisasi ekonomi, termasukmenyusun strategi pembangunan yang baru,dan memperbaiki strukutur internasional menujusistem yang lebih adil dan merata. Untuk ituada beberapa rekomendasi untuk peng-hapusan pekerja anak yang melibatkanpemerintah, masyarakat luas dan stakeholderlainnya.
B. Rekomendasi
Rekomendasi apapun untuk menghapuspekerja anak, terutama dalam sektor informaldi pesisir pantai di Cumpat dan Nambangan,harus mempertimbangkan beberapa faktorpenyebeb dan konteks yang terkait. Faktorekonomi, tradisi, sosialisasi, pendidikan,ketersediaan sumber daya dan peraturan salingterkait dalam membentuk situasi yang sekarangada. Salah satu masalah utama, adalah masihrendahnya kesadaran akan pentingnyapendidikan bagi anak-anak, juga masihtergantungnya pada penghidupan atas hasil lautyang masih bersifat tradisional, serta kurangnyaimplementasi dan sosialisasi peraturan-peraturan tentang perlindungan anak danperaturan perburuhan.
Untuk itu, perhatian yang hanyadifokuskan pada masalah pekerja anak tidakakan efektif dalam menyelesaikan akibat-akibatnegatif dari fenomena pekerja anak. Akantetapi harus dipertimbangkan faktor lain yangberpengaruh terhadap perkembangan anak-
anak. Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkandalam permasalahan pekerja anak diantaranya :
1. Bagi Pemerintah
UU No 23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak perlu ditindak lanjuti denganPeraturan Daerah. Optimalisasi berbagaikebijakan perlindungan anak dimaksud, makadiperlukan koordinasi antara Dinas SosialKota/Kabupaten, Dinas Tenaga Kerja, danPemerintah daerah setempat dalam programperlindungan terhadap Pekerja anak. Monitor-ing dan evaluasi kegiatan sebagai unsur pokokyang melekat terhadap implementasi Undang-Undang dilakukan secara berkala.
2. Bagi LSM/lembaga peduli anak
Masih kurangnya akses bagi anak dankeluarga untuk mendapatkan berbagaiinformasi yang menyangkut kepentingan anak-anak. Hal ini menjadi salah satu faktorpendorong bagi anak-anak untuk bekerja dankurangnya kepedulian keluarga terhadappendidikan, kesehatan dan tumbuh kembanganak. Untuk itu penting sekali membangunwahana serta memberikan informasi,pengetahuan dan keterampilan yang men-dukung kemampuan keluarga untuk pe-menuhan hak anak. Di samping itu perlumengembangkan sebuah wadah bagi anak-anak untuk memberikan ruang ekspresi danproses pembelajaran yang tepat bagi tumbuhkembang mereka.
3. Bagi Masyarakat
Masih rendahnya pengetahuan, pema-haman tentang hak anak serta awarenessterhadap perlindungan anak. Sehingga pentingmembangun solidaritas sosial untuk memberikanperlindungan terhadap hak-hak anak. Salahsatunya adalah dengan mengembangkankomunitas peduli anak, yang memberikanperan aktif dalam perlindungan anak. Melaluikomunitas peduli anak ini diharapkan menjadisebuah movement bagi masyarakat untukmemberikan perhatian yang serius dalampenanganan berbagai permasalahan anakyang mengalami pelanggaran hak.
45
Kondisi Sosial Pekerja Anak (Yanuar Farida Wismayanti)
DAFTAR PUSTAKA
Harry Hikmat, 2004, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Bandung; Penerbit Humaniora
DR. Dedy Mulyana, MA, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung; PT Remaja Rosdakarya
Suyanto, B, 2002, Beban Ganda dan Dilema Guru, Jakarta; Kompas 21 Januari
Suyanto, B, 2002a, Buruh anak di Jawa Timur, Siapa Peduli? Menyambut Hari Anak Nasional 23 Juli2002, Jakarta; Kompas 23 Juli.
Anonim, 2004, Pedoman Penanganan Anak Melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA), Jakarta;Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak Departemen Sosial RI.
Anonim, 2004, Pekerja Anak di Pertambangan Informal di Kutai Barat, Kalimantan Timur, Sebuah KajianCepat, Jakarta; ILO-Kantor Perburuhan Internasional.
Anonim, 2003, Pekerja Anak di India, Laporan Kunjungan ke India, Malang; JARAK
www. Kompas.com
BIODATA PENULIS :
Yanuar Farida Wismayanti, alumnus STKS Bandung tahun 2000, sekarang sebagai staf BidangKerjasama dan Publikasi pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial,Departemen Sosial RI.
46
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 36-46
IMPLEMENTASI AKSESIBILITAS NON FISIK
(PELAYANAN INFORMASI DAN PELAYANAN KHUSUS)
BAGI PENYANDANG CACAT DI ENAM PROVINSI
Haryati Roebyantho
ABSTRAK
Aksesibilitas Non Fisik merupakan kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat sebagaiupaya pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupandan penghidupannya. Kebijakan pemerintah tentang hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 1998 tentang “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang cacat” dan KeputusanMenteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1999 tentang “ Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat danOrang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan”.Aksesibilitas Non Fisik adalah kemudahanPelayanan Informasi dalam bidang : a. Perundang-undangan ;b. Ketenagakerjaan; c. Pendidikan; serta d.komunikasi dan tehnologi. Selain itu juga Pelayanan khusus atau kemudahan dalam menggunakan saranadan prasarana transportasi pelayanan khusus dalam mengikuti pendidikan dan ketenagakerjaan.
Sejak dikeluarkan kebijakan tersebut, beberapa instansi pemerintah dan swasta telah melaksanakanevaluasi. Hasil menyebutkan secara umum yang dievaluasi adalah Aksesibilitas Fisik saja, adapunaksesiblitas non fisik belum mendapat perhatian. Penelitian tentang Penyediaan Aksesbilitas Non Fisik(Pelayanan informasi dan pelayanan Khusus) bagi penyandang cacat bersifat penelitian eksplanasi yaituingin menggali informasi tentang proses implementasi kebijakan pemerintah tentang aksesibilitas NonFisik bagi penyandang cacat dan ingin mengetahui sejauhmana dampak/impak implementasinya. Penentuanlokasi secara purposive berdasarkan kriteria banyaknya jumlah penyandang cacat dan dipilih enam(6)provinsi yaitu: Sumatera Utara; Jawa Tengah; Jawa Timur; Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan NusaTenggara Timur. Pemilihan Responden dilakukan secara purposive berdasarkan kriteria memilikipengetahuan tentang kebijakan aksesbilitas Non Fisik. Pengumpulan data menggunakan metode : wawancara,diskusi kelompok terarah (Fokus group diskusi), studi dokumentasi dan observasi. Analisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aksesibilitas Non Fisik (bunyi, suara, gambar) pada bangunanpelayanan umum (perkantoran, perbelanjaan, perekonomian, pendidikan) dan sarana umum (transportasi)masih sedikit sehingga para penyandang cacat dan keluarganya masih mengalami kendala untuk mengetahuikeberadaan aksesibilitas fisik (pintu khusus, ramp, toilet, pedistrasi dan lift) bagi penyandang cacat. Pelayananinformasi bagi penyandang cacat tentang ketenagakerjaan, pendidikan dan bentuk–bentuk pelayanan khususmasih bersifat lokal dan koneksitas. Implementasi kebijakan belum mampu menformulasikan PeraturanDaerah sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan pusat. Kendalanya antara lain masih kurangnya pemahamandan pengetahuan tentang visi dan misi kebijakan pemerintah sehingga belum mampu memotivasi kesadaranuntuk menyusun Peraturan Daerah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan bagi penyandang cacat.
I . PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hak Asasi Manusia adalah seperangkathak yang melekat pada hakikat keberadaanmanusia sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esadan merupakan AnugerahNya yang wajibdihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi olehnegara, hukum, pemerintah dan setiap orangdemi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia, sebagaimana tercantumdalam Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1(Departemen Kehakiman dan hak AsasiManusia RI, 1999)
Pada kenyataannya terdapat warganegara yang belum mampu meningkatkankesejahteraan, kecerdasan dan keadilan karenakondisi fisik mereka. Salah satunya adalah parapenyandang cacat, dan mereka juga mem-punyai hak dan kesempatan yang sama dalam
47
segala aspek kehidupan dan penghidupansebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 pasal 5 danpasal 7 ayat 1.
Implementasi dari Undang-Undangtersebut tertuang dalam Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 1998 pasal 5, pasal 6 danpasal 7 yang intinya menyebutkan bahwa setiappenyandang cacat mempunyai kesamaankesempatan, kesamaan kedudukan, hak,kewajiban dan peran agar dapat berperan danberintegrasi secara total sesuai dengankemampuannya dalam segala aspek ke-hidupan dan penghidupan. Adapun ke-samaan kesempatan dilaksanakan melaluipenyediaan aksesibilitas. (Himpunan PeraturanPerundang-undangan Penyandang CacatNasional dan Internasional, 2001).
Terdapat dua bentuk aksesibilitas yakniaksesibilitas fisik (aksesibilitas pada: BangunanUmum dan lingkungan, Sarana danTransportasi) dan aksesibilitas Non Fisik(pelayanan informasi dan pelayanan khusus).Fokus penelitian penyediaan aksesibilitas nonfisik yaitu: pelayanan informasi dalam bidangPerundang-undangan, Ketenaga kerjaan,Pendidikan, Komunikasi, dan Teknologi,pelayanan khusus dalam hal pemanfaatansarana dan prasarana angkutan umum bagipenyandang cacat.
Pelayanan informasi diartikan sebagaijenis pelayanan yang berupa suara, bunyi,atautulisan mengenai informasi di bidangPerundang-undangan yang berkaitan denganpenyediaan aksesibilitas pada bangunan umumdan lingkungan serta sarana dan prasaranatransportasi, Ketenagakerjaan, Pendidikan,informasi, Komunikasi, Teknologi dankehidupan sehari-hari. (Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 1998, penjelasan pasal 11ayat <2>a)
Pelayanan Khusus merupakan sarana/fasilitas khusus pada tempat umum yangdiperuntukkan bagi penyandang cacat[(Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998,penjelasan pasal 11 ayat (2b)] dan padafasilitas sarana dan prasarana angkutan umumbaik udara, laut dan darat (Keputusan MenteriPehubungan Nomor KM 71 Tahun 1999).
Keberadaan fasilitas aksesibilitas non fisikbagi penyandang cacat yang disediakan oleh
pemerintah dan masyarakat akan efektif danoptimal apabila para pelaksana peraturanperundang-undangan baik di tingkat pusat(pemerintah Provinsi) dan daerah (pemerintahkabupaten/kota) memiliki pengetahuan danpemahaman tentang hal tersebut.
Mengacu pendapat di atas, padapenelitian ini muncul asumsi bahwa: apabilaterjadi komunikasi yang intensif dan ber-kesinambungan antara pembuat kebijakan(Pemerintah pusat/Eksekutif dan Legislatif)dengan berbagai pihak terkait dalampenyediaan aksesibilitas bagi penyandangcacat, maka implementasi Undang-UndangNomor 4 tahun 1997, Peraturan Pemerintahnomor 43 tahun 1998 dan Keputusan MenhubNomor KM 71 Tahun 1999 sebagai upayapeningkatan kesejahteraan sosial penyandangcacat, khususnya melalui penyediaanaksesibilitas non fisik (pelayanan informasi danpelayanan khusus) dapat terwujud.
Peran komunikasi dalam penelitian iniakan dilihat dari hasil pelaksanaan sosialisasiUndang-Undang Nomor 4 tahun 1997,Peraturan Pemerintah Tahun 1998 danKepmenhub Nomor KM 71 Tahun 1999, yangdiharapkan akan terjadi perubahan pe-ngetahuan dan pemahaman yang positif padapara pejabat Pemerintah Daerah, Perencana,Pengusaha/pengelola bangunan/saranaumum, sehingga mereka memutus kan untukmenyediakan aksesibilitas non fisik bagipenyandang cacat agar penyandang cacatmendapatkan hak, kedudukan, kewajiban danperan yang sama seperti masyarakat normallainnya.
Aksesibilitas non fisik adalah jenispelayanan informasi, meliputi: suara, bunyidan tulisan yang terkait/melekat dengankeberadaan aksesibilitas fisik yang tersedia disarana dan prasarana umum (bandara, stasiun,terminal, kantor pemerintah, kantor Bank,Rumah Sakit, Mall/pertokoan) dan pelayananberbagai informasi di bidang: Perundang-undangan, Ketenagakerjaan, Pendidikan,Komunikasi dan Teknologi dan lain-lain. jenispelayanan khusus bagi penyandang cacat yangmerupakan sarana atau tempat yangdikhususkan untuk para penyandang cacat,yang tersedia di sarana dan prasarana umum(bandara, stasiun, terminal, kantor pemerintah,kantor Bank, Rumah Sakit, Mall/pertokoan),
48
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 47-58
misalnya: loket-loket pembayaran, pemesanantiket, ruang tunggu dan lain-lain.
Terdapat beberapa peraturan per-undangan-undangan sebagai Implementasidari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998yaitu :
a. Undang–Undang R.I. Nomor 18 tahun1999 tentang jasa konstruksi, peraturanuntuk layanan jasa konstruksi perencanaan,pelaksanaan pekerjaan konstruksi, jasakonsultasi pengawasan pekerjaankonstruksi dan pengawasannya);
b. Keputusan bersama antara Menteri SosialR.I. dan Menteri Pekerjaan Umum R.I.Nomor 468/KPTS/1998 tentangPersyaratan Tehnis Aksesibilitas PadaBangunan Umum dan lingkungan(Persyaratan minimal penyediaan aksesi-bilitas bagi penyandang cacat padabangunan dan lingkungan, sertapengawasannya);
c. Keputusan Menteri Perhubungan R.I.Nomor KM 71 tahun 1999 tentangAksesibilitas bagi penyandang cacat danorang sakit pada sarana dan prasaranaperhubungan (penyediaan pelayanankhusus bagi penyandang cacat padasarana dan prasarana transportasi, sertapengawasannya);
d. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 72 Tahun1991 tentang Pendidikan Luar Biasa(Peraturan penyelenggaraan pendidikan,pengelolaan dan pengawasan).
Namun sejak dikeluarkan kebijakanpemerintah tersebut, beberapa instansi baikpemerintah dan swasta telah melaksanakanevaluasi tentang penyediaan aksesibilitasdengan hasil :
a. Aksesibilitas yang sering diadakan evaluasiadalah aksesibilitas fisik.
b. Hasil dari penelitian yang dilaksanakanTim kerjasama antara Himpunan WanitaPenyandang Cacat Indonesia (HWPCI),Yayasan Bina Paraplegia (YANAGIA),FTSP-Usakti dan Ikatan Arsitek Indonesia(IAI) DKI lebih fokus pada kondisiaksesibilitas Fisik (Aksesibel dan sesuai
dengan standar dan spesifikasi). Sedangaksesibilitas non fisik belum tersentuh samasekali.
c. Hasil Penelitian tentang “PermasalahanPenyandang Cacat di Indonesia (Penye-diaan aksesibilitas di lima Propinsi)” yangdilaksanakan Departemen Sosial padatahun 2003 mengemukakan bahwasebagian besar para pejabat dari instansiyang terkait (Dinas Sosial, PemerintahDaerah, Dinas Pekerjaan Umum,Bappeda, Dinas KIMPRASWIL), perencanadan pengelola sarana dan prasaranapelayanan umum(Pimpinan ProyekPembangunan Sarana dan PrasaranaUmum, Ikatan Arsitek Indonesia,AKPINDO) belum memahami dan menge-tahui isi dan makna dari PeraturanPenyediaan Aksesibilitas bagi penyandangcacat. Di sisi lain diketemukan juga bahwaimplementasi dari penyediaan aksesibilitaspenyandang cacat belum dilaksanakansecara konsekuen. (Haryati. R. dkk, 2003).
d. Produk hukum sebagai hasil implementasiKebijakan Pemerintah tentang aksesibilitasbagi penyandang cacat masih fokus padapenyediaan aksesibilitas fisik sedangkanaksesibilitas non fisik belum tersentuh samasekali.
Selain itu masih ditemukan kendala dalampelaksanaan sosialisasi sehingga pelaksanaan-nya belum menyeluruh dan berkesinambungan.Belum efektif pelaksanaan koordinasi lintassektoral dalam mekanisme implementasikebijakan tersebut juga mempengaruhiterwujudnya penyediaan aksesibilitas non fisikbagi penyandang cacat. Oleh karena ituuntuk meningkatkan kesejah-teraan sosialpenyandang cacat dengan prioritas upayamewujudkan kesamaan hak, kedudukan danperanannya, maka dilakukan pengkajiantentang implementasi kebijakan penyediaanAksesibilitas Non Fisik dengan pokokpermasalahan: “Sejauh mana implementasikebijakan Pemerintah tentang AksesibilitasNon Fisik bagi penyandang cacat sertaimplementasinya di Tingkat provinsi dan kota/kabupaten khususnya”
Tujuan mengevaluasi implementasikebijakan aksesibilitas bagi penyandang cacat
49
Implementasi Aksesibilitas Non Fisik (Haryati Roebyantho)
adalah : a. Mengidentifikasi proses implementasikebijakan pemerintah tentang aksesibilitas bagipenyandang cacat; b. Mengidentifikasidampak implementasi kebijakan pemerintah.Agar proses implementasi kebijakan publik bagiPenyandang Cacat mampu memberikan hak,kewajiban dan kesamaan kesempatan untukberperan dalam kehidupan dan penghidupanmaka sasaran penelitian terdiri dari : a. Prosesdan kinerja kebijakan pemerintah tentangpenyediaan aksesibilitas bagi penyandangcacat, dengan fokus pada pelaksanaansosialisasi ( Pusat, provinsi, kota, kabupaten) danproduk hukum yang telah dihasilkan (Pusat,provinsi, kota, kabupaten ); b. Pengetahuan danpemahaman pejabat (eksekutif), legislatif danstake holder tentang kebijakan pemerintahdalam penyediaan aksesibilitas bagipenyandang cacat.
Penelitian ini bersifat eksplanasi yaitu untukmemperoleh gambaran yang lebih jelas tentang: aksesibilitas non fisik bagi penyandang cacatdi beberapa kota di Indonesia, prosesimplementasi kebijakan pemerintah tentangaksesibilitas bagi penyandang cacat dandampak/impak kebijakan serta manfaat bagistake holder (penyandang cacat). Lokasi kajianditentukan secara purposive berdasarkanjumlah penyandang cacat di Indonesia.Dengan demikian dipilih 6 (enam) provinsiyakni: Provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur,Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan NusaTenggara Timur.
Penentuan Sampel responden meng-gunakan teknik purposive berdasarkan kriteria:
a. Instansi/lembaga pemerintah/swastasebagai perumus kebijakan, pelaksanakebijakan dan perencana kebijakan
b. Pelaksana kebijakan misal : perencana/pengelola/pemilik bangunan umum danlingkungan
c. Pelaksana Pelayanan Penyandang Cacat:Pimpinan Panti/Yayasan, guru.
d. Sasaran kebijakan/stake holder atauPenyandang cacat (cacat tubuh, cacatnetra, tuna rungu) yang berusia 20 tahundan mempunyai mobilitas tinggi
Data dan informasi tentang pemetaanaksesibilitas non fisik pada sarana dan
prasarana publik, tempat kerja, dan saranatransportasi dan uraian tentang hambatandalam proses implementasi kebijakan publikdilakukan secara kualitatif.
2. Kerangka Dasar Pemikiran
Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun1997 pasal 1 yang dimaksud denganPenyandang cacat adalah setiap orang yangmempunyai kelainan fisik dan atau mental yangdapat menganggu atau merupakan rintangandan hambatan baginya untuk melakukankegiatan secara selayaknya, yang terdiri daripenyandang cacat fisik, penyandang cacatmental, penyandang cacat fisik dan mental.
Secara hakiki, dalam kehidupanberbangsa dan bernegara keberadaanpenyandang cacat tidaklah berbeda denganwarga masyarakat lainnya. Dengan demikiandalam proses Pembangunan Nasional yangbertujuan mewujudkan masyarakat adil danmakmur yang merata materiil dan spirituilberdasarkan Pancasila dan Undang-UndangDasar 1945, tidak mungkin mengesampingkanpenyandang cacat sebagai obyek maupunsubyek pembangunan. Sebagai warga negaraIndonesia, kedudukan, hak, kewajiban danperan penyandang cacat adalah sama denganwarga negara lainnya. Oleh karena itupeningkatan peran para penyandang cacatdalam pembangunan nasional sangat pentinguntuk mendapat perhatian dan didayagunakansebagaimana mestinya.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9,pasal 10 ayat (1). Pasal 11, pasal 13 dan pasal16 mengatur tentang hak, kedudukan,kewajiban dan peran penyandang cacat dalamkesamaan kesempatan: melaksanakan kegiatandalam aspek kehidupan dan penghidupan(penyediaan aksesibilitas fisik dan non fisik),mengikuti pendidikan, pekerjaan, rehabilitasi,bantuan sosial dan pemeliharaan kesejahteraansosial.
Undang-Undang tersebut masih bersifatumum sehingga dalam mengimplementasikanhal tersebut masih diperlukan formulasikebijakan sebagai petunjuk pelaksanaanperaturan. Oleh karena itu maka Pemerintahmengeluarkan kebijakan tentang upayapeningkatan kesejahteraan sosial bagipenyandang cacat. Menurut prof.
50
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 47-58
Mustopadidjaja, (2003) Kebijakan publikadalah suatu keputusan yang dimaksud untukmengatasi permasalahan tertentu ataumelakukan kegiatan tertentu untuk mencapaitujuan dalam rangka penyelenggaraan tugaspemerintah, Negara dan pembangunan.
Dalam kaitan dengan penelitian ini yangdimaksud dengan Kebijakan Publik tentangAksesibilitas bagi Penyandang cacat adalahdikeluarkan suatu keputusan : berupa formulasiUndang-Undang Nomor 4 tahun 1997sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkanhak-hak penyandang cacat untuk mempunyaikesamaan kesempatan dalam penghidupandan kehidupan (Undang-Undang Nomor 4Tahun 1997, pasal 8, 9 dan 10 ayat 1).Implementasi peraturan tersebut olehpemerintah c/q Departemen Sosial dituangkandalam kebijakan berupa Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 1998 tentang “UpayaMeningkatkan Kesejahteraan Sosial BagiPenyandang Cacat”, khusus mengatur upaya-upaya untuk mewujudkan kemandirian dankesejahteraan penyandang cacat dalampemeliharaan kesejahteraan sosial dankesamaan kesempatan melalui penyediaanaksesibilitas.
Terdapat dua bentuk aksesibilitas yakniaksesibilitas fisik (aksesibilitas pada: bangunanumum dan lingkungannya, sarana danprasarana transportasi) dan aksesibilitas non fisik(Palayanan informasi dan pelayanan khusus).Fokus bahasan pada aksesibilitas non fisikyaitu kemudahan dalam pelayanan informasidi bidang perundangan-undangan, ketenaga-kerjaan, pendidikan, komunikasi dan teknologibagi penyandang cacat serta memberikanpelayanan khusus bagi penyandang cacatdalam mengakses sarana dan prasaranaangkutan umum.
Pelayanan informasi diartikan sebagaijenis pelayanan berupa suara, bunyi, atautulisan mengenai informasi di bidangperundang-undangan yang berkaitan denganpenyediaan aksesibilitas pada bangunan umumdan lingkungannya, sarana dan prasaranatransportasi, ketenagakerjaan, pendidikaninformasi dan tehnologi (Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 1998, penjelasan pasal 11ayat (2).a.)
Pelayanan khusus merupakan sarana/prasarana khusus pada tempat umum yang
diperuntukkan bagi penyandang cacat(Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998,penjelasan pasal 11 ayat (2) b.) dan fasilitasserta pelayanan khusus bagi penyandang cacatpada sarana dan prasarana angkutan umumbaik di darat, laut dan udara (Keputusan MenteriPerhubungan Nomor KM 71 tahun 1999).
Terdapat asumsi bahwa penyediaanfasilitas aksesibilitas non fisik bagi penyandangcacat akan dapat diwujudkan sesuai misi danvisi kebijakan pemerintah apabila para pembuatkebijakan, perencana kebijakan, pelaksanakebijakan dan stake holder memilikipengetahuan dan pemahaman tentangkebijakan tersebut. Adapun pengetahuan danpemahaman tersebut akan terjadi apabilaterdapat komunikasi intensif dan berkesi-nambungan.
Menurut Djafar H Asegaf perankomunikasi mengandung arti memainkanperanan penting dalam mengubah sikap,mengubah nilai dan anggapan yang dapatmendukung terwujudnya perubahan yangdirencanakan (Djafar Assegaf, 1982). Daritulisan Wilburn Schramn diketahui bahwa adatiga peranan penting dalam komunikasi yakni :memberikan informasi, menumbuhkankeinginan untuk menerima gagasan baru danmengajarkan keahlian dalam prosesperubahan. Sedang Everret M Rogersmengatakan bahwa pengaruh komunikasi adatiga yaitu: perubahan terjadi pada pengetahuanpenerima, perubahan terhadap keyakinansehingga penerima memutuskan melakukansuatu tindakan dan perubahan nyata dalammelaksanakan tindakan tersebut.
Mengacu dari ketiga pendapat di atas,asumsi yang digunakan dalam penelitian iniadalah apabila terjadi komunikasi intensifdan berkesinambungan (sosialisasi tentangkebijakan dan koordinasi dalam imple-mentasinya) antara pembuat/perencanakebijakan (pemerintah pusat, eksekutif, legislatifdan yudikatif) maka implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang“Penyandang cacat”, Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 1998 tentang “UpayaPeningkatan Kesejahteraan Sosial bagiPenyandang Cacat”, Keputusan MenteriPerhubungan Nomor Km 71 tahun 1999tentang “ Aksesibilitas bagi penyandang cacatdan orang sakit pada sarana dan prasarana
51
Implementasi Aksesibilitas Non Fisik (Haryati Roebyantho)
perhubungan” dan Undang-Undang Nomor20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional, sebagai upaya meningkatkankesejahteraan sosial penyandang cacat melaluiaksesibilitas/kemudahan non fisik ( pelayananinformasi dan pelayanan khusus) dapat terwujuddengan lancar.
Peran komunikasi akan dilihat dari hasilpelaksanaan sosialisasi kebijakan pemerintah,sehingga terjadi perubahan pengetahuan danpemahaman tentang kebijakan pemerintahtersebut. Kondisi tersebut akan mampumemotivasi perumus/perencana kebijakanmemutuskan untuk mengaplikasikan kebijakantersebut sehingga penyandang cacatmendapatkan hak, kedudukan, peran yangsama seperti masyarakat lainnya.
I I . HASIL PENELITIAN
Uraian hasil penelitian selain meng-gambarkan kondisi aksesibilitas non fisik,Proses dan kinerja kebijakan pemerintahdengan fokus pada : pelaksanaan sosialisasi(Pusat, provinsi, kota, kabupaten); produkhukum yang telah dihasilkan (Pusat, provinsi,kota, kabupaten) dan Pengetahuan sertapemahaman pejabat (eksekutif); legislatif danstake holder tentang kebijakan pemerintahdalam penyediaan aksesibilitas bagipenyandang cacat.
A. Gambaran Kondisi aksesibilitasNon Fisik
Hasil observasi dan wawancara denganpejabat instansi terkait, pengelola bangunanumum, pusat-pusat pelayanan umum (mall,supermaket, perkantoran pemerintah/swasta,rumah sakit, sekolah, panti-panti/yayasan),pusat transportasi (terminal, stasiun,kereta apidan pelabuhan) menunjukkan bahwa sebagianbesar pusat pelayanan umum dan bangunanbelum menyediakan aksesibilitas non fisikberupa bunyi, suara dan tanda gambar,Sehingga para penyandang cacat dan keluargamengalami kesulitan dalam menemukan danmemanfaatkan aksesiblitas/kemudahan yangdisediakan seperti: toilet khusus, lift khusus,ruang tunggu khusus, telpon dan ramp. Dibeberapa pelataran parkir perkantoranpemerintah/swasta, pusat-pusat perbelanjaandan pusat pendidikan sudah terdapat
aksesibiltas non fisik berupa gambar yangmemberitahukan bahwa area tersebutdiperuntukkan bagi kendaraan pengguna kursiroda.
Hasil temuan di lapanganan menunjukkanbahwa terdapat implementasi dari KeputusanMenteri Perhubungan tentang pelayanan khususbagi penyandang cacat sudah ada meskipunmasih dalam standar minimal. BentukAksesibilitas Non Fisik antra lain: ruang tunggukhusus, pelayanan khusus untuk memperolehtiket bagi keluarga penyandang cacat, toilet,disediakannya kursi roda. Pada sarana danprasarana perhubungan laut dan udaraterdapat dua instansi yang menyediakanpelayanan khusus bagi penyandang cacat.Seperti yang dikemukakan oleh Respondenpengelola sarana perhubungan, pelayanankhusus pada sarana dan prasaranaperhubungan yang disediakan berupa: fasilitaspelayanan yang memudahkan penyandangcacat untuk naik dan turun pesawat/kapal,penyediaan kursi roda oleh PT Pelindo (padapelabuhan) dan PT Angkasa Pura padabandara, fasilitas ruang tunggu di stasiun keretaapi, bandara, pelabuhan dan terminal, danfasilitas jalan khusus bagi penyandang cacat.Khusus di Pelabuhan dan di bandara parapenyandang cacat mendapat pelayanan khususdari dua instansi dalam waktu yang bersamaan.Artinya pada area pelabuhan (mulai dari pintumasuk untuk antri tiket, ruang tunggu sampai dipintu masuk kapal) penyandang cacatmendapat pelayanan khusus berupa ke-mudahan mendapatkan tiket, menggunakankursi roda yang telah disediakan di dekat pintumasuk, menggunakan ruang tunggu dan jalanmasuk khusus bagi penyandang cacat yangsemuanya diselenggarakan dan menjaditanggung jawab PT pelindo sebagai instansipengelola pelabuhan. Adapun setelah sampaidi pintu kapal, pelayanan khusus diambil alihkru Pelni sebagai penyelenggara pelayaran.Mereka memberikan kemudahan bagipenyandang cacat dan keluarga untuk masukkapal tidak bersama-sama orang lainnya, didalam kapal mereka diberikan ruangan yangagak luas sehingga memungkinan ruang gerakkursi roda .
Sebagaimana pelabuhan, di Bandarapunpenyandang cacat mendapatkan pelayanankhusus dari dua instansi yaitu di sekitar area
52
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 47-58
bandara dilayani oleh PT Angkasa Pura dansetelah di pesawat dilayani oleh kru maskapaipenerbangan. Umumnya PT. Angkasa Puramenyediakan jalan khusus bagi penyandangcacat dan keluarga, toilet, ruang tunggu dankemudahan mengurus tiket. Adapun penggunakursi roda akan dilayani khusus oleh maskapaipenerbangan dengan menyediakan kursi roda,memberikan kemudahan untuk naik dan turundari pesawat, memberi ruang khusus dipesawat. Kesemuanya sudah tersedia karenapenyediaan aksesibilitas non fisik (Pelayanankhusus) tersebut merupakan standar ataupersyaratan fasilitas sesuai dengan PeraturanPenerbangan Internasional.
Di stasiun kereta api umumnya sudah adabeberapa aksesibilitas non fisik seperti tandagambar bagi pengguna kursi roda di pelataranparkir, tanda gambar yang menunjukkankeberadaan lift khusus bagi pengguna kursiroda, ruang tunggu dan toilet. Namun dalamkenyataannya aksesibilitas tersebut kurangdimanfaatkan, bahkan pada beberapa kotasarana tersebut menjadi kurang terpelihara danrusak atau hilang (misal telpon yang diletakkandi dekat tangga masuk stasiun) yang digunakanuntuk sarana komunikasi antara penyandangcacat dengan penjaga peron. Ruang tungguyang dilengkapi dengan toilet khusus bagipenyandang cacat akhirnya juga tidakterpelihara dan beralih fungsi. Hal inidisebabkan belum diinformasikan adanyaaksesibilitas (ruang tunggu) bagi penyandangcacat (pengguna kursi roda dan pemakaitongkat).
Penyediaan aksesibilitas non fisik(pelayanan informasi) tentang keberadaanaksesibilitas yang dapat dipergunakan olehpenyandang cacat di pusat-pusat pelayananekonomi (mall, supermaket, pasar) belum adasehingga para penyandang cacat mengalamikendala dalam melaksanakan kegiatan ditempat-tempat tersebut apabila merekasendirian. Umumnya para penyandang cacatselalu didampingi keluarga apabila me-ngunjungi pusat-pusat perbelanjaan, sehinggamereka tidak mengalami kesulitan. Meskipunresponden (pengelola mall, managersupermaket) belum pernah mengikuti sosialisasitentang aksesibilitas non fisik bagi penyandangcacat, namun dalam setiap kesempatan paramanager memberikan sosialisasi terhadappelayanan, keamanan dan petugas pusat
perbelanjaan agar memberikan pelayanankhusus terhadap penyandang cacat. Misalmenunjukkan jalan yang bisa dilalui kursi roda,mendahulukan penyandang cacat dan lain-lain.
B. Proses implementasi
Tujuan mengetahui proses Implementasikebijakan aksesibilitas non fisik adalah untukmengetahui tingkat pengetahuan dan pe-mahaman pembuat/perencana/penyusunkebijakan. Indikator yang digunakan pe-laksanaan proses sosialisasi tentang “KebijakanAksesibilitas non fisik serta materi yangdiberikan”. Informasi diperoleh dari respondenpembuat kebijakan (pejabat dari: DepartemenSosial, Departemen Perhubungan, DepartemenPendidikan Nasional, Dinas Ketenagakerjaandan Transmigrasi, KIM PRASWIL/DepartemenPekerjaan Umum); pelaksana kebijakan(pengelola/perencana/pemilik sarana danprasarana bagunan dan pelayanan umumserta perhubungan, lembaga pendidikan khususpemerintah dan swasta). Pelaksanaan sosialisasidan tingkat pemahaman para pelaksanakebijakan merupakan dasar menganalisisproses implementasi kebijakan yang akandideskripsikan berikut ini:
1. Peraturan Perundang-undangan yangmemuat penyediaan aksesibilitas Non Fisikbagi Penyandang Cacat, sifatnya masihumum dan belum menjelaskan secara rincisehingga implementasi di daerahmengalami beberapa kendala. Olehkarena itu untuk mengimplementasikannyadibutuhkan suatu pengetahuan danpemahaman secara menyeluruh maknadari kebijakan tersebut. Pengetahuan danpemahaman visi dan misi suatu kebijakanakan diperoleh melalui sosialisasi.
Hasil wawancara menyebutkanbahwa sosialisasi tentang “KebijakanAksesibilitas Non Fisik bagi Penyandangcacat” masih bersifat lokal dan sektoral. Parapenyusun/pelaksana kebijakan daerah(Dinas Kesejateraan Sosial Provinsi danKota/Kabupaten) di enam lokasi penelitianmengemukakan pernah mendapatkanSosialisasi tentang Undang-Undang Nomor4 Tahun 1997 dan Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 1998. Minimum merekamendapat dua kali sosialisasi yaitu sosialisasi
53
Implementasi Aksesibilitas Non Fisik (Haryati Roebyantho)
oleh Pembuat Kebijakan (Pejabat BiroHumas Departemen Sosial) dan lainnyapada saat sosialisasi Program bagipenyandang cacat (pejabat DirektoratJenderal Rehabilitasi Sosial). Penyusun/Pelaksana kebijakan dari Pemerintah Daerahprovinsi/kota/kabupaten Memperolehsosialisasi pada saat persiapan pelaksanaanprogram bagi penyandang cacat.
Menurut pengelola/perencana saranadan prasarana perhubungan KeputusanMenteri Perhubungan Nomor KM 71 tahun1999 diketahui bukan melalui sosialisasitetapi melalui surat edaran MenteriPerhubungan tentang “PelaksanaanPelayanan khusus bagi penyandang cacatdan orangtua pada sarana dan prasaranaperhubungan”. Menurut mereka surat tersebutjangkauan-nya masih terbatas di lingkungandinas perhubungan pusat, provinsi, kota dankabupaten.
Pelaksanaan Sosialisasi tentangUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem pendidikan juga dilakukandi lingkungan lembaga pendidikanpemerintah/swasta. Sosialisasi dilakukanbersamaan dengan pelaksanaan per-temuan antara dinas pendidikan nasionaldengan orangtua murid dan guru secaraperiodik.
2. Materi sosialisasi yang diberikan oleh BiroHumas Departemen Sosial menyebutkanbahwa sebagian besar menjelaskantentang definisi penyandang cacat danupaya/program Departemen Sosial sepertiRehabilitasi Sosial bagi penyandang cacatoleh Departemen Sosial melalui PusatRehabilitasi di beberapa kota di Indone-sia, Program Rehabilitasi Keliling olehmasing-masing Dinas Sosial provinsi/kota/kabupaten. Latihan keterampilan danvocational, Program bantuan stimulanUsaha Ekonomi Produktif. Adapun materiyang menegaskan tentang hak dankewajiban pemerintah dan swastauntuk menyediakan aksesibilitas bagipenyandang cacat, materi yangmenyebutkan mekanisme implementasikebijakan belum menjadi topik perhatian.
Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3)dijelaskan bahwa menjadi kewajibanpemerintah dan swasta untuk menye-lenggarakan aksesibilitas secara menyelu-ruh, terpadu dan berkesinambungan.Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun1997 tentang Penyandang Cacat telahdimuat tentang mekanisme penyeleng-garaan aksesibilitas, namun belum rinci danjelas dan masih bersifat umum karena belummembedakan antara aksesibiitas fisik danaksesibilitas non fisik. Oleh karena itu masihdiperlukan formulasi kebijakan yangmenjelaskan dan menjabarkan secara rincitentang pelaksanaan penye-diaanaksesibilitas beserta sanksinya berupaPeraturan Daerah (UU Nomor 4 Tahun1997, pasal 15). Adapun sanksi bagipengelola bangunan yang tidakmenyediakan aksesibilitas diuraikan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1998pasal 18 sampai 21.
Menurut pelaksana kebijakan sistempendidikan nasional (Pejabat BidangPendidikan Luar Biasa), saat inidisosialisasikan mengenai pelayanan khususpendidikan melalui sekolah inklusi. Programini merupakan pelayanan khusus pendidikanbagi anak-anak penyandang cacat yangdilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.Sekolah inklusi merupakan keterpaduanatau sekolah yang menye-lenggarakanpendidikan bagi pe-nyandang cacat untukmengikuti sekolah reguler bersama-samadengan anak normal lainnya. Materisosialisasi lebih fokus pada persiapan penye-lenggaraan program inklusi penuh (kelasreguler) yaitu penyandang cacat belajarbersama anak lain (normal) di kelas regulerdengan menggunakan kurikulum reguler, pe-nyiapan keterampilan khusus bagi guruserta manajemen sekolah.
3. Hasil wawancara menunjukkan bahwapemahaman dan pengetahuan parapenyusun/perencana/pelaksana kebijakandi tingkat provinsi/kota/kabupaten dienam kota Medan, Semarang, Surabaya,Banjarmasin dan Kupang tentangkebijakan aksesibiltas non fisik bagipenyandang cacat masih sangat minimserta bersifat lokal dan sektoral. Sebagian
54
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 47-58
besar Responden mengemukakan bahwadikeluarkan kebijakan aksesibilitas adalahuntuk meningkatkan kesejahteraan sosialdan kemandirian para penyandang cacat.Namun ketika ditanyakan lebih mendalammengenai aksesibilitas non fisik sebagianbesar tidak memahami secara rinci kecualipelaksana dari lingkungan perhubungan.Hal tersebut disebabkan oleh beberapahal :
1) Batasan dan definisi tentang aksesibilitasnon fisik belum jelas dan rinci sehinggaoperasionalisasi-nya masih rancu,khususnya tentang pelayanan informasi.Rincian pelaya-nan khusus yang bisadijadikan acuan adalah KeputusanMenteri Perhubungan nomor KM 17tahun 1999 tentang “Aksesibilitas bagipenyandang cacat dan orang sakit padasarana dan prasarana” dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 “tentangSistem pendidikan Nasional”
2) Hampir semua responden me-ngatakanbahwa mereka tidak tahu tentangaksesibilitas non fisik dan belum pernahmendapatkan sosiali-sasi. Hal inimenunjukkan belum efektifnyakomunikasi baik internal maupun lintassektoral sehingga jangkauan sasarankebijakan ter-batas dan sedikit sekaliinformasi yang mampu diserap dandiketahui.
3) Materi sosialisasi belum mampumenginformasikan pentingnyapelaksanaan sosialisasi kebijakanaksesibilitas non fisik dalam upayamewujudkan persamaan kesem-patanbagi penyandang cacat sehingga paraperencana belum memiliki kemauan(good will) untuk mengalokasikan danasosialisasi
Implementasi aksesibilitas non fisik adalahkemudahan dalam pelayanan informasi dankemudahan mendapatkan pelayanan khususbagi penyandang cacat. Tujuan penyediaanaksesibilitas/kemudahan non fisik (pelayananinformasi) adalah untuk memberikan informasiperundang-undangan, pendidikan, ketenaga-kerjaan serta informasi dan komunikasiteknologi. Namun hasil temuan lapanganmenggambarkan bahwa aksesibilitas non fisik
belum begitu dikenal oleh masyarakat(penyusun kebijakan, perencana kebijakan,pengelola kebijakan, stake holder). Adapunaksesibilitas non fisik (pelayanan khusus)bertujuan untuk memberi kemudahan bagipenyandang cacat dalam melaksanakankegiatan sehari-hari. Disamping itu jugamemberi kemudahan bagi penyandang cacatuntuk mengakses pendidikan, ketenagakerjaan,menggunakan sarana dan prasaranatransportasi dan komunikasi.
Umumnya mereka belum mengetahui danmemahami pengertian aksesibilitas non fisik(pelayanan informasi). Namun beberaparesponden menyebutkan adanya beberapapelayanan khusus bagi penyandang cacat,seperti: pelayanan khusus di bidang ke-sejahteraan sosial; pelayanan khusus di bidangpendidikan; pelayanan khusus di bidangtransportasi dan komunikasi sebagai berikut:
a. Bidang Kesejahteraan Sosial
Berdasarkan PP nomor 43 Tahun1998, upaya peningkatan kesejahteraansosial bagi penyandang cacat melalui: (a)rehabilitasi sosial dalam panti danluar panti (UPSK dan Loka Bina Karya); (b)bantuan sosial berupa UEP danpengembangan KUBE, bantuan peng-asramaan murid SDLB. Menurut pejabatDinas Kesejahteraan Sosial (Medan,Semarang, Surabaya, Makasar,Banjarmasin), informasi tentang pe-layanankesejahteraan sosial bagi penyandang cacatmasih terbatasdi lingkungan sasaran Program Rehabili-tasi Keliling, Bantuan KUBE-PACA, Programvokasional di pusat Rehabilitasi Penyandangcacat dan program-program vokasional diPanti-panti baik pemerintah maupun swasta.
Menurut penyandang cacat,informasi yang diberikan masih terbataspada program-program yang dilak-sanakan Departemen Sosial RI, DinasKesejahteraan Sosial Provinsi , kota dankabupaten. Pelayanan yang diberikanberupa rehabilitasi dan latihan kete-rampilan serta bantuan usaha ekonomisproduktif. Umumnya informasi dilak-sanakan bersamaan dengan rapatkoordinasi dengan penyuluh-penyuluhsosial, pelayanan rehabilitasi keliling dan
55
Implementasi Aksesibilitas Non Fisik (Haryati Roebyantho)
lingkupnya masih terbatas. Keterbatasaninformasi tentang pelayanan bagipenyandang cacat menyebabkankesulitan bagi penyandang cacat yangtidak memenuhi kriteria yang diper-syaratkan padahal mereka membutuhkanketerampilan tersebut. Kondisi ini jugamenyebabkan tidak semua penyandangcacat di daerah tersebut mendapatkanpelatihan karena keter-batasan dana.
b. Bidang Pendidikan
Sebagaimana bidang lainnya,pelayanan informasi tentang pelaksanaanpendidikan bagi penyandang cacat belummenjangkau masyarakat luas. Hasil temuanmenyebutkan bahwa terdapat pelayanankhusus bagi penyandang cacat untukmengikuti pendidikan sesuai dengankecacatannya. Sejak tahun 2003 terdapatprogram baru bagi penyandang cacat yaitusekolah inklusi. Penyampaian informasitentang program-program pendidikankhusus bagi penyandang cacat masihterbatas pada saat rapat koordinasi antarguru dan para orang tua murid secaraperiodik. Selanjutnya informasi tersebut olehpara guru disebarkan dilingkungan kerabatdan teman dekat, sehingga masyarakatumum lainnya (keluarga yang memilikipenyandang cacat dan butuh pelayanankhusus) tidak mengetahui program tersebut.
c. Bidang Ketenagakerjaan
Menurut pejabat Dinas Tenaga KerjaInformasi tentang program pelatihan tenagakerja melalui Balai LatihanKerja BLK. Setelah mereka mem-peroleh keterampilan mereka bisamengikuti program magang padaperusahaan-perusahaan sesuai dengan jeniskecacatan dan kemampuannya.Perusahaan-perusahaan yang dapatdijadikan tempat latihan/magang adalahperusahaan yang memilki nota kerjasamadengan Dinas Tenaga Kerja dan DinasSosial. Dalam penelitian belum di-dapatkaninformasi jelas tentang pelayanan khususbagi penyandang cacat di bidangketenagakerjaan.
d. Bidang Transportasi
Pelayanan informasi tentang kebijakanMenteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun1999 tentang aksesi-bilitas bagi penyandang cacat danorang sakit pada sarana dan prasaranaperhubungan hanya diberikan di lingkunganpelaksana kebijakan (pengelola,perencana) sarana dan prsaranaperhubungan (laut, darat dan udara).Sedangkan pelayanan khusus bagipenyandang cacat secara sederhana sudahdisediakan seperti penyediaan kursi roda (dipelabuhan dan Bandara); adanya ruangtunggu khusus, toilet khusus dan lift khusus.
C. Permasalahan dalam implementasi
Sebagaimana termuat dalam PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang“Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosialbagi Penyandang Cacat”, penyediaanaksesibilitas (fisik dan non fisik) menjaditanggung jawab pemerintah dan masyarakatdan pengawasan serta pengendalian di-laksanakan oleh dan menjadi tanggung jawabGubernur kepala Daerah Tingkat I. Tercantumpula aturan yang menyebutkan bahwa untukmekanisme palaksanaan penyediaan aksesi-bilitas bagi penyandang cacat akan diatur lebihlanjut pada Peraturan Daerah.
Hasil wawancara dengan para pembuatkebijakan di tingkat propinsi, kota/kabupatenmenunjukkan bahwa penerapan otonomidaerah masih menimbulkan keanegaragamanpersepsi tentang kewenangan dan skalaprioritas pembangunan. Akibatnya terjadikesenjangan baik dalam komunikasi danpemahaman tentang kewenangan dan fungsipemerintah daerah, sehingga implementasikebijakan tentang aksesibilitas Non Fisik bagipenyandang cacat kurang mendapat perhatiankarena bukan merupakan prioritas perhatianserta baru dalam wacana atau prosespenyusunan Peraturan Daerah tentangpelaksanaan penyediaan aksesibilitas bagipenyandang cacat.
Di sisi lain keterbatasan anggaran,sumber daya manusia, jangkauan sosialisasibelum menyeluruh menyebabkan kurangnyapengetahuan tentang aksesibilitas non fisik.Di beberapa daerah disebutkan bahwa
56
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 47-58
penyediaan aksesibilitas non fisik dirasakanbelum merupakan keperluan yang urgen/penting sebab para penyandang cacatumumnya kurang membutuhkan pelayanankhusus atau pelayanan informasi khusus padasarana dan prasarana transportasi karenamereka selalu didampingi keluarga kalaubepergian.
Terdapatnya keragaman dalam me-mahami kebijakan tentang aksesibilitas non fisikbagi penyandang cacat khususnya pengelolasarana pelayanan umum yang mengganggapbahwa penyediaan aksesibilitas merupakantanggung jawab pemerintah bukan tanggungjawab pengelola sarana pelayanan umum.Kurangnya pemahaman dan pengetahuantentang fungsi pelayanan informasi danpelayanan khusus bagi penyandang cacatsehingga penyandang cacat mengalamiketerbatasan dalam mengakses programataupun menggunakan fasilitas umum.
I I I. PENUTUP
Berdasarkan beberapa temuan dilapangan dapatlah disimpulkan secara garisbesar sebagai berikut:
A. Kesimpulan
1. Implementasi kebijakan tentangaksesibilitas non fisik bagi penyan-dang cacat di tingkat provinsi/kota/kabupaten belum sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan.
2. Kurangnya pemahaman dan penge-tahuan para pembuat/perencana ke-bijakan di tingkat pusat tentang maknadan tujuan penyediaan aksesibilitasnon fisik bagi penyandang cacatmenyebabkan kurangnya perhatian danmotivasi untuk menyusun Peraturan Daerahtentang aksesibilitas Non fisik sebagai
penjabaran dari UU Nomor 4 Tahun 1997tentang “ Penyandang Cacat”; PP Nomor43 Tahun 1998 tentang “UpayaPeningkatan Kesejahteraan Sosial BagiPenyandang Cacat” KepmenHub NomorKM71 Tahun 1999 tentang “ penyediaanAksesibilitas pada sarana dan prasaranaperhubungan”.
3. Pelaksanaan sosialisasi belum menyeluruhdan masih bersifal lokal dan sektoral,menyebabkan kurangnya informasitentang program-program pemerintahuntuk para penyandang cacat, akibatnyapenyandang cacat mengalami keter-batasan dalam mengakses pendidikan,latihan keterampilan, bekerja magang ,mendapat rehabilitasi dan bantuan.
4. Penyediaan aksesibilitas pada bangunandan lingkungan masih sangat minim danbelum sesuai dengan standart minimalpenyediaan aksesibilitas. Hal tersebutmenyebabkan penyandang cacat meng-alami kesulitan dalam melaksanakankegiatan.
B. Rekomendasi
1. Pelaksanaan sosialisasi akan optimal danefektif apabila dilakukan secarakoordinatif antara Departemen Sosial,Departemen Perhubungan, DepartemenTenaga Kerja dan Transmigrasi,Departemen Pendidikan Nasional.KIMPRASWIL, lembaga dan yayasan.Pelaksanaannya bersifat menyeluruh,kontinyu secara berjenjang dan lintassektoral.
2. Menyusun mekanisme implementasikebijakan sehingga menghasilkanformulasi Perda, Surat KeputusanGubernur atau Surat Keputusan Bupati.
57
Implementasi Aksesibilitas Non Fisik (Haryati Roebyantho)
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsini, 1987, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktis. Jakarta; Bina Aksara.
Depertemen Sosial RI, 1977, Laporan Penyuluhan Hukum Yang berkaitan dengan Undang-UndangNomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; Jakarta; Biro Hukum.
—————— 1997, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1977 tentang Penyandang Cacat. Jakarta;Biro Hukum.
Dunn William,1999, Analisis Kebijakan publik , Yogyakarta; Gadjah Mada university Press.
Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia, 2001, Himpunan Peraturan Perundang-undanganPenyandang Cacat Nasional dan Internasional, Jakarta.
Islamy. M Irfan, 2000, prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta; Sinar Grafika.
Roebyantho Haryati, dkk. 2003, Permasalahan Penyandang Cacat di Indonesia (aksesibilitas di limakota), Jakarta; Pusat Penelitian Permasalahan.
Syahrir, 1987, Kebijakan Negara Kosistensi dan Implementasi, Jakarta; LPES.
Winarno Budi, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta; Media Presindo.
BIODATA PENULIS :
Haryati Roebyantho, Alumnus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial danIlmu Politik, Jurusan Sosiatri. Kini Ajun Peneliti Madya pada Pusat Penelitian dan PengembanganKesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen SosialRI.
58
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 47-58
PROFIL WKSBM DALAM UPAYA MENINGKATKAN
KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT DI YOGYAKARTA(Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul)
Suyanto
ABSTRAK
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah sistem kerjasama pelayanankesejahteraan sosial di tingkat akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringanpendukungnya. Wahana ini dapat berupa jejaring kerja kelembagaan sosial komunitas lokal baik yangtumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkanoleh pemerintah pada tingkat lokal, sehingga lembaga yang terbentuk tersebut dapat mensinergikanpelaksanaan tugas-tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial. Sesuai dengan definisi di atas, maka sasaranidentifikasi ini dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) Perkumpulan sosial yang tumbuh dari komunitassendiri atau yang ditumbuhkan dari pihak luar yang berada di komunitas lokal (desa/kelurahan); (2) Nilaisosial budaya lokal, meliputi adat istiadat, tradisi dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
Dari hasil kajian diperoleh gambaran mengenai profil WKSBM khususnya yang berada di KabupatenGunung Kidul adalah sebagai berikut: (1) WKSBM di Kabupaten Gunung Kidul sudah ada dan berkembangdi masyarakat lebih dari 10 tahun; (2) Jumlah kelompok WKSBM di tiap-tiap desa rata-rata diatas 50kelompok perkumpulan; (3) WKSBM yang ada dibentuk dan tumbuh ditengah-tengah masyarakat sebagaiupaya pengintegrasian masyarakat dalam rangka mempertahankan kondisi ketahanan masyarakat danpada umumnya memiliki criteria keanggotaan menempati atau berdomisili pada wilayah tertentu; (4)Kegiatan WKSBM kebanyakan bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan sosialmasyarakat dengan cara meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang dibiayai dengan iuran anggotanyasendiri; (5) Kegiatan WKSBM diwarnai dan dijiwai semangat kebersaman yang intinya ingin membantuorang lain dan kegotong royongan.
Keadaan ini menunjukkan bahwa di masyarakat telah tersedia wahana atau potensi yang dapatdimobilisasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun masih memerlukan beberapa sentuhanintervensi dari pemerintah dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, menejemen pelayanankesejahteraan sosial serta penggalian sumber dana.
I . PENDAHULUAN
Ketika kondisi perekonomian nasionaldalam keadaan normal, kebijaksanaan pem-bangunan lebih diarahkan pada paradigmapembangunan yang meng-andalkan padapertumbuhan ekonomi. Ketika itu pendekatanpembangunan kesejahteraan yang digunakanadalah residual approach yakni pelayanan sosialdiberikan manakala permasalahan sosial sudahmuncul. Gaya pendekatan seperti itumenyebabkan pembangunan kesejahteraansosial yang diemban Departemen Sosialterkesan charity dan terlambat. Setelahmengalami krisis ekonomi sejak tahun 1997menyebabkan sumber daya moneter menjaditerbatas, akibatnya anggaran yang disediakan
untuk Departemen Sosial juga menjadi terbataspula. Menyadari kondisi tersebut, paradigmapembangunan yang perlu dikembangkanadalah pembangunan yang berpusat padamasyarakat atau yang dikenal dengan istilahPeople Centered Development (PCD). Dalamprogram ini partisipasi masyarakat menjadiperhatian pemerintah. Salah satu strategi yangdikembangkan dalam konsep pendekatan PCDadalah pemberdayaan masyarakat terutamayang menjadi sasaran pelayanan sosial adalahWahana Kesejahteraan Sosial BerbasisMasyarakat, Pranata Sosial atau perkumpulansosial. Seperti diketahui bahwa pranata socialyang ada dan eksis di masyarakat saat ini dapatdikatakan sebagai wadah atau tempat untukmemberikan pelayanan sosial;
59
Pranata sosial menurut Paulus Wirotomo(2004) mengutip definisi Selo Soemarjanadalah sebagai kumpulan nilai dan norma yangmengatur suatu bidang kehidupan manusia.Sedangkan Pranata Sosial di ditinjau dari segikebudayaan melalui pendekatan ethnoscienceatau cognitive anthropology diartikan sebagaipola bagi tindakan dan tingkahlaku manusiayang dilakukan pada suatu tempat. Dengandemikian pengertian pranata sosial juga dapatdisebut sebagai kebudayaan karena pranatasosial berisikan seperangkat pengetahuanmanusia yang berupa sistem nilai-nilai, resep-resep, blue-print, dan norma-norma sertaaturan-aturan yang terdapat didalam kepalamanusia sebagai pengetahuan kebudayaan,yang diperoleh melalui proses belajar dalamkehidupan sosialnya, dan digunakan sertadijadikan pedoman tindakan tingkah lakunya,dalam upaya untuk memenuhi kebutuhanhidupnya, serta digunakan untuk memahami,memanipulasi dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di lingkungan hidupnya.Dengan uraian seperti tersebut diatas dapatdijelaskan melalui skema dibawah ini:
Skema: Pranata Sosial ditijau dari konsep kebudayaan.
Pranata sosial ini bila diartikan secarasempit ada yang berbentuk formal dan non for-mal. Pranata sosial formal biasanya dibentukatas prakarsa kebutuhan pelayanan yangbiasanya keberadaannya didukung pemerintahdaerah bahkan sampai di tingkat pusat atauorganisasi yang besar yang bertaraf nasionaldan bahkan internasional. Pranata sosial nonformal dibentuk atas prakarsa wargamasyarakat setempat berdasarkan atas etnistertentu, agama, profesi, kebutuhan wargamasyarakat tertentu. Oleh karena itu dalambeberapa tahun terakhir ini Departemen SosialRI sudah mulai mengarahkan program-programnya pada strategi pemberdayaanmasyarakat yang melibatkan pranata sosial.Pembangunan kesejahteraan sosial secaranasional memandang kemiskinan sebagai suatumasalah yang perlu mendapat penangananserius karena merendahkan martabatkemanusiaan. Demikian juga dalam kerangkapembangunan kesejahteraan sosial, kemiskinanmerupakan suatu akar dari masalahkesejahteraan sosial lainnya, walaupun terdapatbanyak masalah kesejahteraan lain yangberkaitan erat dengan masalah kemiskinan.
Kebudayaan = Nilai, norma, perasaan dan lain-lain
Status
Peran
Perasaan/Ide yang diwujudkan melalui
tingkah laku/tindakan di suatu tempat
Informal
Formal
Kelembagaan/ Perkumpulan
yang merupakan wahana kessos
Institution
Institusi
Pranata Sosial Pranata Sosial
60
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 59-72
Pembangunan nasional sebenarnya telahberhasil menurunkan jumlah penduduk miskinmenjadi 11,3 persen atau 22,5 juta padatahun 1996. Hal tersebut mendorongpemerintah untuk lebih meningkatkan kinerja-nya dalam upaya menghapus kemiskinandengan dicanangkannya kebijaksanaan“Memantapkan Program Menghapus Ke-miskinan” (MPMK) pada sidang Kabinet terbatastanggal 22 April 1997. Dimana operasionalkebijaksanaan menghapus kemiskinan tersebutpada intinya meliputi kegiatan ProgramKeluarga Sejahtera, Program Inpres DesaTertingga (IDT), dan Program KesejahteraanSosial (PROKESOS), Program Pendidikan danLatihan serta berbagai program terkait lainnya.Program-program tersebut merupakan bagiandari tiga kelompok kebijaksanaan pem-bangunan yang luas (Laporan terpaduPROKESRA, 1997).
Sebagaimana kita ketahui bahwa Pro-gram Keluarga Sejahtera yang dikenal denganTAKESRA dan KUSESRA dimotori oleh BKKBN,kemudian Program IDT pelaksanaannyadikembangkan Bappenas. SedangkanDepartemen Sosial RI sendiri mempunyai tugasdan tanggung jawab mengenai PROKESOS.Program kesejahteraan sosial yang telahdilaksanakan untuk mengatasi masalahkemiskinan semenjak REPELITA III namanyaBimbingan dan Pembangunan Kesejah-teraan Masyarakat serta Usaha SwadayaSosial Masyarakat (BPKM-USSM). SetelahDepartemen Sosial berdiri lagi Programkesejahteraan sosial oleh Direktorat Pem-berdayaan, Departemen Sosial RI mulaimengembangkan pembangunan yang berpusatpada masyarakat atau yang dikenal denganistilah People Centered Development (PCD).Pemberdayaan yang terpusat pada masyarakatini terutama ditujukan kepada pembinaanWahana Kesejahteraan Sosial BerbasisMasyarakat, namun dalam pelaksanaannyaternyata baru dalam tahap pendataan. WahanaKesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakatdiharapkan dapat berperan aktif dalammeningkatkan ketahanan sosial masyarakat.Karena dari berbagai studi menunjukkan bahwaperanan Wahana Kesejahteraan Sosial BerbasisMasyarakat sangat besar dalam pembangunanmasyarakat. Masyarakat tergerak untukberpartisipasi dengan cara partisipasi itudilakukan melalui perkumpulan yang sudahdikenalnya atau yang sudah ada di tengah-
tengah masyarakat. Sebaliknya pelaksanaansuatu kegiatan ditingkat masyarakat akankurang berhasil secara optimal bila mana tidakmelibatkan dan memperhitungkan keberadaanWahana Kesejahteraan Sosial BerbasisMasyarakat. Peran aktif kelompok lokal ini lebihjauh lagi dapat memfasilitasi persatuan nasionaldan mengakomodasi tuntutan berbagaikelompok untuk partisipasi, berpolitik danpengaturan diri yang lebih mandiri.
Wahana kesejahteraan sosial berbasismasyarakat adalah system kerjasamapelayanan kesejahteraan sosial di tingkat akarrumput yang terdiri atas usaha kelompok,lembaga maupun jaringan pendukungnya.Wahana ini dapat berupa jejaring kerjakelembagaan sosial komunitas lokal baik yangtumbuh melalui proses alamiah dan tradisionalmaupun lembaga yang sengaja dibentuk dandikembangkan oleh pemerintah pada tingkatlokal, sehingga lembaga yang terbentuk tersebutdapat mensinergikan pelaksanaan tugas-tugasdi bidang usaha kesejahteraan sosial. Sesuaidengan definisi Wahana Kesejahteraan SosialBerbasis Masyarakat di atas, maka sasaranidentifikasi ini dapat dikategorikan sebagaiberikut:
1. Perkumpulan sosial yang tumbuh darikomunitas sendiri atau yang ditumbuhkandari pihak luar yang berada di komunitaslokal (desa/kelurahan).
2. Nilai sosial budaya lokal, yang meliputiadat istiadat, tradisi dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
Meskipun beberapa studi berhasilmenunjukkan peran aktif dan memberikontribusi Wahana Kesejahteraan SosialBerbasis Masyarakat dalam pembangunankesejahteraan sosial, namun demikian sampaisaat ini belum tersedia adanya data tentangkeberadaan Wahana Kesejahteraan SosialBerbasis Masyarakat, baik dalam jumlah,bentuk dan tipologi atau model-modelkegiatannya.
Pada tahun 1997/1998 dengan ter-jadinya krisis moneter dan berkembangmenjadi krisis ekonomi, masalah kemiskinankembali meningkat, karena banyak pendudukjatuh kembali ke dalam kemiskinan. Pada bulanApril 1998 menurut BPS jumlah penduduk miskinbertambah menjadi 79,4 juta jiwa atau 33,9%
61
Profil WKSBM dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat di Yogyakarta (Suyanto)
dari seluruh penduduk yang jumlahnyamencapai 202 juta (Kepala BPS, Sigito Soewito,MA).
Dalam kaitan ini Departemen Sosial RImelalui pembangunan Kesejahteraan Sosialtelah sejak REPELITA IV melaksanakanpengentasan kemiskinan sesuai dengan amanatkonstitusi yang dikenal dengan ProgramKesejahteraan Sosial melalui Kelompok UsahaBersama (PROKESOS KUBE). Sedangkansecara nasional pengentasan kemiskinan padaintinya adalah kegiatan Program KeluargaSejahtera, Program IDT, PROKESOS, ProgramPendidikan dan Latihan serta program terkaitlainnya. Program-program tersebut merupakanbagian dari 3 (tiga) kelompok kebijaksanaanpembangunan yang luas (Laporan terpaduPROKESRA 1997).
PROKESOS pada dasarnya adalah pro-gram pengentasan kemiskinan terhadappenyandang masalah kesejahteraan sosialmelalui pendekatan kelompok warga ataukeluarga binaan sosial yang telah dibina melaluiproses kegiatan untuk melaksanakan kegiatankesejahteraan sosial dan Usaha EkonomiProduktif (UEP) dalam semangat kebersamaansebagai sarana untuk meningkatkan tarafkesejahteraan sosial.
Secara kuantitas jumlah WKSBM adadisemua Lokasi Kelurahan yang ada di DIYogyakarta Namun sejauh mana data dan pro-gram WKSBM tersebut belum diperolehinformasi. Disamping itu bagaimana metodedan teknik pemberdayaan masyarakat tersebutdapat dilaksanakan, yang mungkin sudahdilihat secara internal pada programimplementer perlu diinventarisasi dan dievaluasisebagai masukan bagi pengembangan pro-gram pemberdayaan dimasa-masa yang akandatang, oleh sebab itu Pusat KetahananSosial Masyarakat Badan Pelatihan DanPengembangan Sosial pada awal tahun tahun2006 mengadakan kegiatan mengidentifikasiprofil dan kegiatan WKSBM dalam pem-bangunan kesejahteraan sosial karenadipandang perlu untuk dilakukan penelitianselanjutnya.
Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasipelaksanaan WKSBM yang sebagian besaradalah bentukan warga yang tumbuhnya darimasyarakat lokal dan sesuai dengankebutuhan. Selain itu juga ingin mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaankegiatan, sehingga program dapat berjalansesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.Penelitian ini dilaksanakan di KabupatenGunung Kidul.
I I . METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatanpartisipasif. Adapun sifat penelitiannya adalahdiskriptif kualitatif dengan pokok bahasannyaadalah hasil pelaksanaan pendataan programpemberdayaan untuk WKSBM/perkumpulansosial yang bergerak di bidang usahakesejahteraan sosial dan bantuan pemberianpelayanan bagi masyarakat melaluipendekatan kelompok swadaya masyarakat ditingkat desa/kelurahan. Fokus telaahan padakondisi WKSBM, Struktur organisasi, sumberdana, kondisi tenaga, proses pelaksanaanpemberdayan dan manfaat atau keberhasilanusaha dalam meningkatkan ketahanan sosialmasyarakat di lingkungannya.
Pemilihan sample lokasi ditentukan secarapurposif berdasarkan adanya program yangmenjadi sasaran penelitian yang telahmelaksanakan kegiatan usaha kesejahteraansosial. Adapun sample lokasi terpilih yakni diempat Desa yang berlokasi di empatKecamatan: Empat Desa tersebut adalah(1) Desa Balearjo, di Kecamatan Wonosasi;(2) Desa Watusigar, di Kecamatan Ngawen;(3) Desa Playen di Kecamatan Playen dan (4)Desa Tepus di Kecamatan Tepus. Pemilihanresponden juga ditentukan secara purposif danjumlah responden sebanyak 349 orangsemuanya dari pengurus atau anggotakelompok salah satu perkumpulan.
Teknik pengumpulan data menggunakantiga cara yakni: (a) Wawancara, (b) StudiDokumentasi dan (c) observasi. Analisamenggunakan analisa kualitatif dalammendiskripsikan kondisi kelompok.
Ada lima aspek yang menjadi perhatiandalam pengkajian ini, lima aspek tersebutadalah: (1) Aspek identitas perkumpulan sosialatau wahana kesejahteraan sosial berbasismasyarakat; (2) Aspek keanggotaan; (3) AspekSumber daya dan dana; (4) Aspek programdan kegiatan lembaga; dan (5) Aspek jaringankerja.
62
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 59-72
I I I. HASIL PENELITIAN
A. Monografi Daerah Penelitian
Wilayah Daerah Istimewa Yogyakartamemiliki luas wilayah 3.185,80 km2 atau 0,17%dari luas Indonesia. Wilayah Daerah IstimewaYogyakarta dibagi dalam 4 Kabupaten dan 1Kota, yaitu: Kabupaten Kulonprogo denganluas wilayah 586,85 km2 (18,40%), denganjumlah penduduk 448.091 jiwa; KabupatenBantul dengan luas wilayah 506,85 km2(15,91%), dengan jumlah penduduk 789.745jiwa; Kabupaten Gunungkidul dengan luaswilayah 1.485,36 km2 (46,62%), denganjumlah penduduk 751.423 jiwa; KabupatenSleman dengan luas wilayah 574,82 km2(18,04%), dengan jumlah penduduk 874.195jiwa; dan Kota Yogyakarta dengan luas wilayah32,50 km2 (1,02%), dengan jumlah penduduk874.798 jiwa.
Pada tahun 2002 Propinsi DIY denganjumlah penduduk sebanyak 3.374.968 jiwamerupakan daerah terpadat ke dua di Indone-sia setelah DKI. Pada akhir tahun 2002 tercatatjumlah rumahtangga 769.265.
Mata pencaharian penduduk beranekaragam mata pencaharian dan tidak ada matapencaharian penduduk yang mayoritas. Matapencaharian penduduk adalah petani,peternak, usaha warungan (dagang), homeindustri, dagang candak kulak, karyawan,pertukangan dan lain-lain.
B. Identitas Kelembagaan PerkumpulanSosial di Lokasi Daerah Penelitian
Kajian Wahana Kesejahteraan SosialBerbasis Masyarakat di Kabupaten GunungKidul dilakukan di 4 (empat) desa. Daripendataan tersebut diperoleh 349 kelompokatau perkumpulan sosial (Wahana Kesejah-teraan Sosial Berbasis Masyarakat/WKSBM)yang ada di masyarakat. Terhimpun dalam 23jenis kelompok/perkumpulan sosial yangdikategorikan dalam Wahana KesejahteraanSosial Berbasis Masyarakat. Jenis-jeniskelompok tersebut dapat dilihat pada tabelberikut ini:
Tahun Berdiri
< 10 Tahun > 10 Tahun Jumlah No Jenis Kelompok
Jml % Jml % Jml %
1 Dasa Wisma 6 31,60 13 68,40 19 100
2 Posyandu 2 15,40 11 84,60 13 100
3 PKK 3 6,25 45 93,75 48 100
4 KUBE 12 40,00 18 60,00 30 100
5 Pemuda 10 55,60 8 44,40 18 100
6 Tani 1 6,67 14 93,33 15 100
7 Sinoman 1 14,30 6 85,70 7 100
8 Pengajian 6 28,60 15 71,40 21 100
9 Rukun Tetangga 6 6,45 87 93,55 93 100
10 Usia Lanjut 1 100,00 0 0 1 100
11 IDT 0 0 6 100,00 6 100
12 Persekutuan Doa 1 25,00 3 75,00 4 100
13 Kesenian 7 33,30 14 66,70 21 100
14 Paguyuban Warga Dusun 1 9,09 10 90,01 11 100
15 Siskamling 0 0 18 100,00 18 100
16 PKBM 0 0 1 100,00 1 100
17 LPMD 2 100,00 0 0 2 100
18 Keluarga Muda Mandiri 1 100,00 0 0 1 100
19 Klompencapir 0 0 1 100,00 1 100
20 Olahraga 2 20,00 8 80,00 10 100
21 Rukunwarga 0 0 6 100,00 6 100
22 Budaya/Adat 0 0 2 100,00 2 100
23 BPD 1 100 0 0 1 100
Jumlah 63 18,10 286 81,90 349 100
Tabel 1.
Kelompok/Perkumpulan Sosial (WKSBM) di Empat Desa Pada Kabupaten Gunung Kidul.
63
Profil WKSBM dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat di Yogyakarta (Suyanto)
Dari data pada tabel tersebut dapatdiketahui bahwa tahun berdirinya sebagianbesar 68,4 % atau sebanyak 13 jenis WKSBMtelah berumur atau berdiri lebih dari 10 tahun;yang berumur kurang dari 10 tahun ada 6lembaga perkumpulan (WKSBM) atau sebesar31,6%. Keadaan ini menunjukkan bahwakepentingan/kebutuhan bersama telah lamadirasakan dan diupayakan dicarikan jalanpemecahannya yang dilakukan secarabersama-sama dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok tersebutbiasanya dimulai dari tingkat Rukun Tetangga,Dasawisma, kelompok PKK dan usahabersama. Semua kelompok tersebut dibentukuntuk memenuhi kebutuhan anggota. Tujuanpembentukan kelompok ada bermacam-macan sesuai kebutuhan masyarakat dalamupaya meningkatkan ketahanan sosialmasyarakat melalui peningkatan kesejahteraanwarganya. Untuk itu masing-masing WKSBMatau kelompok sosial memiki identitas yangberbeda dapat diuraikan satu persatu dari tujuandidirikannya lembaga sosial tersebut sebagaiberikut:
1. Perkumpulan dasawisma; Tujuandiririkannya Dasawisma ini memilikiidentitas kelompok yang beranggotakankurang lebih 10 Kepala Keluarga (KK),pada umumnya anggotanya terdiri darikaum wanita dan ibu rumahtangga.Kegiatan yang dilakukan umumnya berupapertemuan rutin dengan acara arisan,simpan pinjam, tabungan, ceramahkeagamaan atau usaha-usaha yangbertujuan meningkatkan pendapatankeluarga.
2. Perkumpulan Posyandu (Pos PelayananTerpadu), kelompok ini biasanyaberanggotakan ibu-ibu rumahtangga yangmemiliki anak balita. Kelompok ini dibentukoleh masyarakat atas prakarsa daripemerintah. Tujuan kelompok ini untukmeningkatkan kesehatan anak danmeningkatkan kesejahteraan ibu dananak. Selain itu pada umumnya memilikikegiatan pemeriksaan kesehatan balita,menimbang balita, pelayanan keluargaberencana dan penyuluhan peningkatangizi keluarga.
3. PKK, Kelompok ini beranggotakan kaumwanita dan ibu rumahtangga, tujuan
kelompok ini adalah usaha peningkatankesejahteraan keluarga melalui berbagaikegiatan seperti arisan, simpan pinjam,tabungan, gotong royong, usahaekonomis produktif yang dikerjakan olehibu-ibu/kaum wanita. Mempunyaijangkauan wilayah berjenjang dari tingkatRukun Tetangga, Rukun Warga, Dusun,Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupatendan Propinsi.
4. KUBE (Kelompok Usaha Bersama),kelompok ini pada umumnya ber-anggotakan 10 kepala keluarga darikeluarga kurang mampu (miskin) yangmemiliki usaha kecil-kecilan. Kelompok inidibentuk untuk memingkatkan penghasilandengan kegiatan utama adalah ekonomiproduktif. Pembentukan kelompok inipada umumnya diprakarsai olehpemerintah melalui proyek-proyek tertentu.
5. PEMUDA. Kelompok ini dibentuk olehmasyarakat dengan anggota yangmemiliki criteria keanggotannya berusiatertentu yaitu antara usaia 19 tahun sampaidengan usaia 40 tahun. Kelompokpemuda ini pada umumnya memilikikegiatan edukatif, ekonomis produktif danrekreatif.
6. TANI. Kelompok ini dibentuk olehmasyarakat atas prakarsa pemerintahdalam upaya peningkatan hasil pertanian.Kelompok ini beranggotakan para petanidan memiliki kegiatan usaha peningkatanpenghasilan.
7. Seniman. Perkumpulan warga masyarakatyang memiliki minat dan bakat dibidangkesenian baik kesenian tradisional maupunkesenian modern seperti jathilan, karawitan,keroncong, kethoprak dan sejenisnya.Kelompok kesenian ini memiliki kegiatanlatihan rutin dan pentas untuk mengisiacara permintaan atau acara-acaratertentu. Kelompok kesenian ini padaumumnya beranggotakan orang dewasa.
8. Pengajian. Kelompok ini terdiri dari majlisTa’lim dan Takmir masjid. Kelompok inidibentuk oleh masyarakat untuk me-ningkatkan ketakwaan kepada Tuhan YangMaha Esa bagi kaum muslim. Kegiatanyang dilakukan kelompok ini diantaranyaadalah mengadakan pengajian.
64
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 59-72
9. Rukun Tetangga. Kelompok ini merupakanlembaga integrasi masyarakat terkecil,yang beranggotakan sejumlah KepalaKeluarga, bertugas membantu pemerintahmengintegrasikan warganya dan mem-berikan pelayanan kepada wargamasyarakat dalam urusan kepemerintahanseperti: memberikan surat keterangandomisili dan lain sebagainya. Dalammengintegrasikan warganya kelompok inimemiliki kegiatan kemasyarakatan sepertipertemuan berkala, arisan, gotong-royong, urusan kematian dan lain-lainnya.
10. Kelompok Lansia. Tujuan dibentuknyakelompok lansia ini oleh masyarakatbertujuan untuk meningkatkan kesejah-teraan lanjut usia dengan cara mem-berikan pelayanan kegiatan pemeriksaankesehatan bagi para lansia, senam sehatbagi lansia serta kegiatan dalam upayapengembangan konsep “tua berguna”.
11. IDT. Kelompok ini dibentuk pemerintahdalam rangka meningkatkan kualitashidup masyarakat desa tertinggal.
12. Persekuatuan Doa. Tujuan dibentuknyakelompok ini adalah untuk meningkatkanketakwaan terhadap Tuhan Yang MahaEsa bagi kaum kristiani. Kegiatan yangdilakukan kelompok persekutuan doaadalah kegiatan keagamaan dankegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan.
13. Kesenian. Kelompok ini terdiri darikumpulan warga masyarakat yangmempunyai minat dan bakat dibidangkesenian baik itu kesenian tradisionalmaupun modern. Kelompok ini memilikikegiatan latihan rutin dan pentas untukmengisi acara permintaan atau acara-acara tertentu, misalnya peringatan hari-hari besar nasional.
14. Kelompok Paguyuban Warga Dusun.Kelompok ini dibentuk oleh masyarakatdengan tujuan untuk bermusyawarahdalam menyelesaikan berbagai persoalanyang muncul. Tetapi pada umumnyabanyak yang berfungsi sebagai “wahanarembug desa”. Biasanya kelompok iniberanggotakan bapak-bapak danmengadakan pertemuan setiap 35 harisekali atau setiap (bahasa jawa “selapan”)hari sekali. Pada acara pertemuan rutin
tersebut biasanya diisi dengan acara-acara rembug desa, arisan, simpan pinjamdan lain sebagainya sesuai keperluan.
15. Siskamling (Kelompok system keamananlingkungan). Kelompok ini dibentukmasyarakat dengan tujuan memenuhikebutuhan akan rasa aman. Kelompok inipada umumnya beranggotakan priadewasa berusia di atas 19 tahun.
16. PKBM (Pendidikan Ketrampilan BerbasisMasyarakat). Kelompok ini dibentukpemerintah dengan tujuan pembe-rantasan buta huruf namun didalampelaksanaannya tidak hanya pem-berantasan buta huruf saja.
17. LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masya-rakat Desa). Kelompok ini dibentukdengan prakarsa dari pemerintah dengantujuan untuk mengkoordinasikan pem-bangunan di tingkat desa.
18. Keluarga Muda Mandiri. Kelompok inidibentuk oleh pemerintah melalui programUP2WKSS dengan tujuan meningkatkanderajat kesehatan dan kesejahteraanwanita dan keluarga.
19. Klompencapir. Kelompok ini dibentukmasyarakat atas prakarsa pemerintahdalam rangka peningkatan pengetahuanpetani sehingga dapat meningkatkan hasilpertaniannya.
20. Olahraga. Kelompok ini dibentukmasyarakat untuk mewadahi kegiatansesuai dengan minat dan bakat wargamasyarakat dalam bidang olah raga.Pada umumnya memiliki kriteriakeanggotaan usia tertentu yakni antara19 – 40 tahun.
21. Rukun Warga. Kelompok ini merupakanlembaga integrasi masyarakat, yangberanggotakan sejumlah Rukun Tetangga(RT), bertugas membantu pemerintahmengintegrasikan warganya dan mem-berikan pelayanan kepada wargamasyarakat dalam urusan kepemerintahanseperti: memberikan surat keterangandomisili dan lain sebagainya. Dalammengintegrasikan warganya kelompok inimemiliki kegiatan kemasyarakatan sepertiarisan, gotong-royong, urusan kematiandan lain-lainnya.
65
Profil WKSBM dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat di Yogyakarta (Suyanto)
22. Budaya/Tradisi/Adat. Kelompok inimemiliki kegiatan yang tumbuh danberkembang ditengah-tengah masyarakatsecara turun temurun merupakan kegiatanrituan untuk mengucapkan syukur danmemohon keselamatan dari Tuhan YangMaha Esa. Kegiatan tradisi/adat/budayaini biasanya berupa sesaji yang dilakukansecara berkelompok, seperti bersihdusun/desa, rasulan, sedekah laut dan se-jenisnya. Anggota dari kelompok iniadalah seluruh kepala keluarga yangberdomisili pada lingkup wilayah tertentu.
23. BPD. Kelompok ini merupakan BadanLegislatif di tingkat desa yang bertugasuntuk bersama-sama dengan perangkatdesa menentukan kebijaksanaan pem-bangunan desa.
Dari jumlah jenis perkumpulan tersebut diatas paling banyak adalah kelompok rukuntetangga dengan jumlah 93 kelompok atausebesar (26,65%), diikuti kelompok PKK denganjumlah 48 kelompok atau sebesar (13,75%),kemudian diikuti KUBE, (Pengajian dan
kesenian), Dasawisma, (Pemuda danSiskamling). Keadaan ini menunjukkan bahwaikatan kelompok berdasar pada “kewilayahan”yaitu Rukun Tetangga dan “kepentingan/kebutuhan bersama dalam kelompok kecil”seperti Rukun tetangga, PKK, Dasawisma, KUBE,dan lain-lain.
Sedangkan jika dilihat dari tujuan daripembentukan kelompok ada bermacam-macam, yakni: untuk meningkatkan kesejah-teraan anak, Kesejahteraan ibu dan anak,Kesejahteraan lansia, Peningkatan pendapatanintegrasi masyarakat dan untuk memenuhikepentingan atau kebutuhan lain-lainya.Keadaan ini menguatkan anggapan bahwaperkumpulan/kelompok tersebut dibentuk olehmasyarakat dengan tujuan untuk memenuhikepentingan/kebutuhan bersama anggotanya.
C. Keanggotaan
Keanggotaan perkumpulan sosial hasilkajian adalah jumlah anggota, kriteria anggota,syarat menjadi anggota, pendidikan danperiode kepengurusan. Akan diuraikan berikut:
Tabel 2.
Jumlah Anggota Kelompok Sosial
Jumlah Anggota
< 10 orang 11 – 20 orang >20 orang Jumlah No Jenis
Kelompok Jml % Jml % Jml % Jml %
1 Dasa Wisma 0 0 16 84,21 3 15,79 19 100
2 Posyandu 0 0 2 15,40 11 84,60 13 100
3 PKK 0 0 7 14,60 41 85,40 48 100
4 KUBE 7 23,33 6 20,00 17 56,67 30 100
5 Pemuda 0 0 5 27,80 13 72,20 18 100
6 Tani 1 6,67 5 33,33 9 60,00 15 100
7 Sinoman 0 0 5 71,40 2 28,60 7 100
8 Pengajian 0 0 1 4,76 20 95,20 21 100
9 Rukun Tetangga 0 0 4 4,33 89 95,67 93 100
10 Usia Lanjut 0 0 0 0 1 100 1 100
11 IDT 0 0 0 0 6 100 6 100
12 Persekutuan Doa 1 25 0 0 3 75 4 100
13 Kesenian 0 0 6 27,30 16 72,70 21 100
14 Paguyuban Warga Dusun 0 0 0 0 11 100 11 100
15 Siskamling 0 0 0 0 18 100 18 100
16 PKBM 0 0 0 0 1 100 1 100
17 LPMD 0 0 0 0 2 100 2 100
18 Keluarga Muda Mandiri 1 100,00 0 0 0 0 1 100
19 Klompencapir 0 0 0 0 1 100 1 100
20 Olahraga 0 0 0 0 10 100 10 100
21 Rukunwarga 0 0 0 0 6 100 6 100
22 Budaya/Adat 0 0 0 0 2 100 2 100
23 BPD 0 0 1 100 0 0 1 100
Jumlah 10 3,40 57 16,20 282 80,40 349 100
66
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 59-72
Dari data tersebut yang merupakan hasilkajian diketahui bahwa semua respondenmengatakan mengetahui jumlah anggotanyadengan pasti. Dari data yang ada pada 23jenis perkumpulan tersebut ternyata jumlahanggota lebih dari 20 orang yaitu darikelompok rukun tetangga. Sedang yangberanggotakan antara 11-20 orang terbanyakadalah dasawisma.
Syarat menjadi anggota kelompokperkumpulan sosial ternyata sebagian besar(90,83%) atau sebanyak 317 kelompokdidasarkan pada domisili di wilayah tertentu.Sedangkan sebagian kecil kelompok untukmenjadi anggota suatu kelompok yangmensyaratkan anggotanya dengan ber-dasarkan pada pendidikan ada sebesar4,29% atau sebanyak 15 kelompok, diikutidengan yang memiliki kekayaan sebesar 4,87%atau sebanyak 17 kelompok. Dari perkumpulankelompok sosial yang menyatakan tidakmemiliki persyarakat untuk menjadi anggotakelompok sosial ternyata terbanyak darianggota kelompok dari Rukun Tetangga, PKKdan Dasawisma. Keadaan ini menunjukkanbahwa untuk menjadi anggota kelompok tidakdituntut persyaratan yang berat, kriteria anggotakelompok cukup berdomisili/bertempat tinggaldi wilayah tertentu. Karena perkumpulan inidibentuk oleh masyarakat sehingga persyaratankeanggotaannya dan kepengurusannya diatursendiri oleh kelompok tersebut berdasarkankesepakatan bersama. Dalam menentukanperiode kepengurusanpun paling banyakadalah kurang dari 5 tahun sebesar 87,96%atau sebanyak 307 kelompok; lainnya selamaperiode 6 – 10 tahun sebanyak 24 atau sebesar6,87% diikuti selama lebih dari 10 tahunsebanyak 18 kelompok atau sebesar 5,16%.Terhadap jawaban pertanyaan yang menjawabterhapap kepengurusan kelompok dipegangatau dijabat lebih dari 10 tahun ini menunjukkanbahwa kepengurusan tersebut memiliki masakerja yang tidak ditentukan/tidak tentu; hal inimenunjukkan bahwa pengelolaan perkumpulanmasih sangat sederhanna dan belum mengacupada aturan-aturan yang jelas, biasanya masihberdasarkan saling percaya dan menghormatiyang tua, sehingga yang ditunjuk sebagaiketua/pengurus kelompok adalah tokoh yangdisegani atau dianggap tua, tanpa melihatkemampuan untuk mengelola perkumpulan.Perkumpulan seperti ini biasanya masih sangat
konvensional, tradisional dan berjalan berdasarpada kebiasaan-kebiasaan yang telah dijalani,tanpa ada upaya pengembangan baik pro-gram maupun kegiatannya.
D. Sumber Daya
Sumber daya dari perkumpulan sosial darihasil kajian yang dapat diuraikan ada duayakni: sumber daya manusia dan sumber dana.Sumber daya manusia dapat dilihat dari segipendidikan dan usia. Dari segi pendidikananggota masing-masing perkumpulanrenponden menjawab lebih dari satu tingkat/jenjang pendidikan dimana yang terbanyakadalah tingkat pendidikan yang ditamatkanadalah SLTA kemudian diikuti yangberpendidikan SLTP dan Sekolah Dasar.Sedangkan dari segi usia anggota masing-masing perkumpulan memiliki anggota yangyang berbanyak berusia antara 19 – 39 tahunsebesar (40,80%) atau sebanyak 217 anggotadan yang berusia 40 – 60 tahun ada sebanyak196 orang atau sebesar 36,80%. Inimenunjukkan bahwa potensi yang dapatdikembangkan untuk meningkatkan kinerjaperkumpulan.
Jika dilihat dari sumber dana masing-masing kelompok memiliki sumber dana dariiuran anggota dan dari sumbangan masya-rakat sekitar. Ini menunjukkan bahwa kemauananggota berkorban untuk kelangsungankegiatan kelompoknya cukup besar.
E. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan kelompok/perkumpulan sosial tidak dapat disajikan dalambentuk data angka karena jawaban yangdiperoleh semuanya jawaban dari pertanyaanyang terbuka dan jawabannya sangatlahberagam. Namun program dan kegiatanperkumpulan tersebut kebanyakan selarasdengan jenis kelompoknya. Kegiatan yangdilakukan kelompok/perkumpulan tersebutterbanyak adalah kegiatan arisan dan simpan-pinjam dan kegiatan keagamaan. Kegiatantersebut dilakukan seperti kelompok PKK,Dasawisma, Rukun Warga, Rukun Tetangga,arisan, paguyuban baik dusun maupun desarata-rata mempunyai kegiatan arisan dansimpan-pinjam sebagai pengikat dan bahanpertemuan kelompok.
67
Profil WKSBM dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat di Yogyakarta (Suyanto)
Hampir semua program dan kegiatanyang dilakukan perkumpulan sosial ditujukanuntuk mensejahterakan anggota dengan caramengutamakan memberikan pelayanankebutuhan orang anggota dari pada kebutuhanorang yang memerlukannya namun bukananggota kelompok. Hal ini dikarenakanketerbatasan sumber daya, sarana yang dimilikiperkumpulan-perkumpulan sosial tersebut.Meskipun demikian dapat dikatakan hampirsemua program dan kegiatan telah me-nunjukkan upaya-upaya penanganan masalahsosial dengan metoda “case work” dan “groupwork”. Jika kita telusuri perkumpulan-perkumpulan tersebut telah memiliki konsepdasar pekerjaan sosial, hanya saja mereka tidaktahu apa yang harus dikerjakan danbaggaimana cara pengem-bangannya.
F. Nilai-Nilai Sosial Budaya
Dari berbagai kepentingan/kebutuhan/persoalan yang dirasakan oleh masyarakatmenumbuhkan keinginan kelompok untukmemecahkan kepentingan secara bersama-sama. Berbagai kepentingan itu berupakebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhanuntuk hidup, kebutuhan rasa aman, kebutuhanaktualisasi diri dan sebagainya. Keinginanuntuk memecahkan kepentingan/kebutuhanmerupakan masalah yang perlu diselesaikanmelalui pembentukan perkumpulan sosial yangtujuannya antara lain untuk meningkatkankesejahteraan anggotanya. Keinginan untukmemecahkan masalah secara bersama-samaini bersumber pada nilai-nilai kebersamaanyang dimiliki dan dikembangkan di tengahmasyarakat dan merupakan kebiasaanmasyarakat sejak jaman nenek moyangnya;nilai-nilai tersebut antara lain hasrat mem-bantu orang lain yang sedang kesusahan, ke-percayaan untuk saling pinjam-meminjam
barang atau uang, menyampaikan informasiatau berita yang baik atau buruk, dukamaupun suka, gotong royong dan lainsebagainya. Hasil kajian mengenai nilai-nilaisosial budaya tersebut dapat diuraikan sebagaiberikut.
Dari data yang diperoleh dari hasil kajianmenunjukkan bahwa sebagaian besarresponden mengatakan nilai solidaritan perludipertahankan dengan cara membantu warga/anggota perkumpulan yang terkena musibahsebanyak 260 responden atau sebesar 28,70%;dikuti responden yang memberikan jawabannilai-nilai solidaritas diberikan/dilakukan melaluikegiatan gotong royong sebanyak 292 atausebesar 32,30%. Angka tersebut membuktikanbahwa kelompok/perkumpulan sosial tersebutsungguh-sungguh dijiwai oleh nilai-nilai yangbertujuan untuk membantu orang lain melaluikegiatan gotong royong. Keadaan inimerupakan potensi kesetiakawanan sosial yangdapat dikembangkan sebagai potensi dansumber kesejahteraan sosial sebagai wahanauntuk meningkatkan ketahanan sosial di tingkatlocal dengan tanpa menunggu uluran tangandari pemerintah.
G. Jaringan Kerja
Dari hasil kajian dilokasi pendataan dapatdiketahui bahwa Wahana kesejahteraan sosialberbasis masyarakat dapat dikatakan belumtampak adanya jaringan kerja antar kelompok/perkumpulan sosial yang ada, kecualikelompok-kelompok yang terbentuk karenaadanya intervensi dari pemerintah yangsebagian telah membentuk jaringan kerja,namun jaringan kerja itu masih terbatas dengankelompok sejenis. Untuk lebih jelasnya dapatdilihat pada tabel berikut:
68
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 59-72
Dari hasil pendataan kurang dari 50%atau sebanyak 158 kelompok sosial jaringankerja terbentuk karena adanya bantuan darikelompok atau lembaga lain atau merupakankegiatan berjenjang dari tingkat Rukun Tetanggasampai Kabupaten atau Propinsi contohnyakelompok PKK. Jaringan kerja bentukanpemerintah biasanya berupa jaringan sejenisvertikal (berjenjang) seperti kelompok RT, RW,PKK. Sedangkan yang horizontal seperti PPKP,PHBS, UPPKS, PKBM.
Sebagian kegiatan bertumpu padasumber-sumber lokal maka keberadaankelompok-kelompok bentukan masyarakat lebihdiwarnai dengan dukungan lokal, kebanyakansumber-sumber yang digalipun lebih banyakpada intern anggota mereka atau donatur yangmerasa terikat oleh kewajiban moral. Dukungandari pemerintah terhadap perkumpulan sosialmasih sangat terbatas pada perkumpulanbentukan masyarakat yang diprakarsai olehpemerintah setempat.
H. Pembinaan Kelompok
Langkah-langkah pembinaan untukmemberikan motivasi dan melatih tenaga kerjaatau dalam memberikan jasa nasehat yangdiberikan kepada pengurus kelompoksebaiknya terlebih dahulu dikaji agar dengankebutuhan dan permintaan anggota kelompok.Karena tujuan pembinan ini adalah pelatihandalam bentuk pengelolaan, pemasaran hasilproduksi, penggunaan teknologi danpengelolaan keuangan. Program pembinaanharus juga ditunjang dengan adanya bahanbaku atau alat peragaan.
Berdasarkan hasil penelitian ternyatapembinaan kelompok di Kab. Gunung Kidulselama ini masih terbatas pada pendataan.Padahal menurut pejabat dari Dinas Sosialmereka para pengurus kelompok perlumendapatkan pembinan dan bantuan stimulanuntuk digulirkan kepada anggota kelompok.Selain itu juga perlu adanya forum komunikasi
Tabel 3.
Jaringan Kerja Kelompok Sosial di Lokasi Kajian.
Jaringan Kerja Kelompok Sosial
Organisasi Sosial Pemerintah Jumlah No Jenis Kelompok
Jml % Jml % Jml %
1 Dasa Wisma 3 42,90 4 57,10 7 100
2 Posyandu 0 0 9 100 9 100
3 PKK 6 20,70 23 79,30 29 100
4 KUBE 0 0 26 100 26 100
5 Pemuda 6 85,70 1 14,30 7 100
6 Tani 0 0 6 100 6 100
7 Sinoman 3 100 0 0 3 100
8 Pengajian 7 100 0 0 7 100
9 Rukun Tetangga 4 14,30 24 85,70 28 100
10 Usia Lanjut 0 0 1 100 1 100
11 IDT 0 0 6 100 6 100
12 Persekutuan Doa 1 100 0 0 1 100
13 Kesenian 1 100 0 0 1 100
14 Paguyuban Warga Dusun 4 100 0 0 4 100
15 Siskamling 0 0 5 100 5 100
16 PKBM 0 0 1 100 1 100
17 LPMD 0 0 2 100 2 100
18 Keluarga Muda Mandiri 0 0 1 100 1 100
19 Klompencapir 0 0 1 100 1 100
20 Olahraga 0 0 4 100 4 100
21 Rukunwarga 0 0 6 100 6 100
22 Budaya/Adat 0 0 2 100 2 100
23 BPD 0 0 1 100 1 100
Jumlah 35 22,20 123 77,80 158 100
69
Profil WKSBM dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat di Yogyakarta (Suyanto)
yang tujuannya untuk komunikasi edukasi dantukar informasi antar kelompok sosial yangsejenis maupun yang heterogen. Denganpemberian stimulan tersebut dari Dinas Sosialkhususnya perlu memonitoring kegiatan danpenggunaan dana bagi kelompok sosialdengan cara mengadakan pendataan danmengidentifikasi kelompok sosial yang ada.
I. Manfaat Kelompok Sosial bagiAnggota
Manfaat yang dirasakan antar anggotakelompok dapat dilihat dari segi ekonomi dansosial. Dari segi sosial adalah meningkatnyarasa kebersamaan dan kegotongroyonganyang satu dengan yang lainnya sedangkanmanfaat dari segi ekonomi adalah adanyafasilitas untuk mendapatkan pinjaman baikbarang, uang maupun tenaga. Hal inidikarenakan jenis kelompok sosial yang merekaikuti berbeda, juga karena ketrampilan anggotauntuk mengembangkan kelompok jugaberbeda.
Selain memiliki manfaat ekonomi, dilihatdari segi sosial tampak meningkatnyakemampuan berorganisasi dan bertambahnyateman. Disamping itu pengetahuan anggotakelompok juga meningkat seiring denganseringnya mengikuti pertemuan yang diadakanuntuk membahas persoalan dan hambatanyang timbul dalam kegiatan yang dilaksanakansecara rutin.
IV. PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian diatas dapat di ambilkesimpulan sebagai berikut:
1. WKSBM di Kabupaten Gunung Kidulsudah ada dan berkembang dimasyarakat lebih dari 10 tahun.
2. Jumlah kelompok WKSBM di tiap-tiapdesa rata-rata diatas 50 kelompokperkumpulan.
3. WKSBM yang ada dibentuk dan tumbuhditengah-tengah masyarakat sebagaiupaya pengintegrasian masyarakatdalam upaya mempertahankan kondisiketahanan masyarakat dan padaumumnya memiliki kriteria keanggotaanmenempati atau berdomisili pada wilayahtertentu.
4. Kegiatan WKSBM kebanyakan bertujuanuntuk meningkatkan ketahanan sosialmasyarakat dengan cara meningkatkankesejahteraan anggotanya dengan caradibiayai dengan iuran anggotanya sendiri.
5. Kegiatan WKSBM diwarnai dan dijiwaioleh semangat ingin membantu orang laindan kegotong royongan
Keadaan ini menunjukkan bahwa dimasyarakat telah tersedia wahana atau potensiyang dapat dimobilisasi untuk meningkatkankesejahteraan sosial. Namun masih memerlukanbeberapa sentuhan intervensi dari pemerintahdalam hal peningkatan kualitas sumber dayamanusia, manajemen pelayanan kesejahteraansosial serta penggalian sumber dana.
B. Rekomendasi
Pembangunan di Indonesia bukan hanyamerupakan tanggung jawab pemerintah saja,partisipasi serta keterlibatan semua lapisanmasyarakat sangatlah diharapkan. PeranKelompok Sosial saat ini sudah diakui olehpemerintah daerah, mengingat kegiatan-kegiatan nyata yang dilakukan sangatmembantu terlaksananya program pem-bangunan terutama dalam menciptakanketahanan sosial.
Peluang dan kesempatan untuk ber-partisipasi dalam pembangunan masih sangatluas mengingat kompleksnya permasalahandan jumlah serta luas wilayah golonganekonomi lemah masih sangat banyak. Tinggalbagaimana pemerintah menyikapi hal itu agarprogram-program yang dilakukan kelompok-kelompok sosial yang ada di daerahmendapatkan dukungan dari pemerintah secarapenuh dan dapat dimanfaatkan sebagai
70
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 59-72
pendamping program peningkatan kesejah-teraan sosial yang yang ada di daerah-daerah.Untuk itu pemerintah perlu memperhatikankelembagaan yang ada di daerah dengancara:
1. Memberikan pelatihan bagi penguruskelompok sosial.
2. Perlu memberikan bantuam stimulan untukdigulirkan kepada anggota kelompoksosial yang ada.
3. Perlu dibentuk forum yang tujuannya untukmembentuk wadah/sarana komunikasi,edukasi dan memberikan informasi antarkelompok sosial di tingkat lokal baik untukkelompok yang sejenis maupun yangheterogen.
4. Perlu adanya monitoring dari pemerintahdalam bentuk pendataan dan peng-identifikasian kelompok sosial yang adadi daerah kekuasaannya.
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Syarwani dan Meuthia Gani Rochman. 1992. Pembangunan Swadaya Nasional, Jakarta;LP3ES.
Anonim. 1997. Peranan Program Kesejahteraan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan MelaluiKUBE, Jakarta; Dit. Bin Bansos.
………………………. 1998. Menteri Sosial RI Pada Sidang Kabinet terbatas Memantapkan ProgramMenghapus Kemiskinan, Jakarta; Dit. Bin Bansos.
……………………… 2003. Pola Penanggulangan Kesejahteraan Sosial Menteri Sosial RI, Jakarta;Departemen Sosial RI.
Dorojatun Kuntjoro-Yakti. 1996. Kemiskinan di Indonesia. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
Florus, Paulus, et.al. 1994. Kebudayan Dayak Aktualisasi dan Transpormasi, Jakarta; LP3S-IDRD denganPT.Grasindo.
Larso, Wursito. 1995. Pemerataan Pembangunan Antara Harapan dan Kenyataan. Bergetar, Solo.
Sutopo HB. 1993. Konsep Pembangunan Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan DitinjauDari Sudut Sosiologi Pembangunan Antara Peluang dan Tantangan. Bergetar, Solo.
Twikromo, Argo. 1993. Pembangunan Masyarakat dan Pembangunan Kepemimpinan Kelompok.Bergetar, Solo.
Prastiwi, Etty. 1993. Wanita Dalam Peranannya Sebagai Kader Pembangunan dan Ibu Rumah Tangga.Bergetar, Solo.
Maryanto, 1996. Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Ekonomi Rakyat Lewat Jaringan. Bergetar,Solo.
Muhammd, Rusdin. 1993. Kelembagaan Desa Sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat, Bergetar, Solo.
Wardani, Nila. 1993. Sebuah Bentuk Dampingan Bagi Wanita Pekerja Industri Rumah Tangga, Bergetar,Solo.
Midgley, James, 2005. Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial,Jakarta; Diperta Islam Departemen Agama.
71
Profil WKSBM dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat di Yogyakarta (Suyanto)
Nurdin dan Suradi, 2004. Penelitian Peranan Organisasi Lokal Dalam Pengembangan Masyarakat,Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol.9, No.01, Pusbang UKS,Balatbang, Departemen Sosial RI.
Korten, David.C, 1982. Pembangunan Berpusat Pada Rakyat, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
Wirotomo, Paulus, 2004. Makalah Kontruksi Jaring Pranata Sosial Untuk Penguatan Ketahanan Sosial(Kerangka Konseptual), Jakarta.
BIODATA PENULIS :
Suyanto, Alumnus Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikProgram Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tahun 1989, kini Ajun Peneliti Madya pada PusatPengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Pendidikan dan Penelitian KesejahteraanSosial, Departemen Sosial RI.
72
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 59-72
PEMANFAATAN POTENSI MASYARAKAT MELALUI PERAN
SERTA MASYARAKAT DI DESA LANGENSARI, KECAMATAN
LEMBANG, KABUPATEN BANDUNG
Ivo Noviana
ABSTRAK
Permasalahan kesejahteraan sosial selalu ada dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali dalamsuatu lingkungan masyarakat. Beragam potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa yang dapatdimanfaatkan untuk membantu pengembangan dan kemandirian desa mereka, antara lain adanya lembagaatau institusi sosial, serta nilai-nilai yang mendukung pembangunan seperti nilai kebersamaan, gotongroyong dan kesetiakawanan. Apabila potensi tersebut tidak dapat dijaga maka akan memudar dan mungkinakan menghilang. Oleh karena itu dibutuhkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan potensi yangada. Sehingga masyarakat dapat mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di lingkunganmereka.
I . PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan kesejahteraan sosialmerupakan bagian yang tidak terpisahkan daripembangunan nasional yang diselenggarakansebagai bagian dari upaya mewujudkanintegrasi sosial melalui peningkatan ketahanansosial dalam tata kehidupan dan penghidupanbangsa Indonesia. Dalam Pola DasarPembangunan Kesejahteraan Sosial ditegaskanbahwa hakikat pembangunan kesejahteraansosial adalah upaya peningkatan kualitaskesejahteraan sosial perorangan, kelompok dankomunitas masyarakat yang memiliki harkat danmartabat, dimana setiap orang mampumengambil peran dan menjalankan fungsinyadalam kehidupan.
Tujuan dari pembangunan di bidangkesejahteraan sosial adalah terwujudnya tatakehidupan dan penghidupan yang me-mungkinkan bagi setiap warga untukmengadakan usaha dan memenuhi kebutuhandasar hidupnya, baik perorangan, keluarga,kelompok dan komunitas masyarakat denganmenjunjung tinggi hak asasi manusia serta nilaisosial budaya setempat. Untuk mewujudkantujuan tersebut, secara bersama-samamasyarakat dapat menggunakan potensi yangdimilikinya dalam usaha meningkatkankesejahteraan diri sendiri dan lingkungan
sosialnya. Hal ini dapat dicapai apabilamasyarakat berperan serta dalam prosespembangunan.
Pembangunan desa sebagai suatukegiatan yang terus menerus memerlukanadanya penggerak dari dalam masyarakat itusendiri (inner will ). Sifat paternalistik,kesetiakawanan dan semangat gotong royongmerupakan nilai-nilai yang masih terdapatdalam kehidupan masyarakat di perdesaan danhal ini juga merupakan potensi yang ada padamasyarakat desa yang saat ini sudah jarangditemui pada masyarakat perkotaan.
Dalam pembangunan masyarakatterdapat tiga unsur yang sangat penting, yaitu :(1) mengutamakan inisiatif masyarakat; (2)mengutamakan swadaya masyarakat; dan (3)memanfaatkan sumber-sumber dan potensiyang ada di lingkungan setempat. Dapatdikatakan bahwa pada hakikatnya pem-bangunan masyarakat desa dapat dilakukandengan menggunakan potensi dan sumberdayayang ada. Namun persoalan yang sering terjadiadalah kadangkala potensi tersebut tidakterkenali dengan baik, sehingga potensi dansumberdaya yang ada sering kali tidakdidayagunakan secara optimal. Oleh karenaitu, pengenalan terhadap potensi yang dimilikimasyarakat sangat dibutuhkan untukdimanfaatkan dalam pemecahan masalahkesejahteraan sosial yang ada.
73
B. Permasalahan
Pada dasarnya, masyarakat mempunyaibanyak potensi baik dilihat dari sumber-daya alam, sumberdaya manusia, maupunsumberdaya sosial dan budaya. Perma-salahannya adalah potensi-potensi apa sajayang terdapat pada masyarakat DesaLangensari dan bagaimana peran serta darimasyarakat untuk pemanfaatan potensimasyarakat Desa Langensari KecamatanLembang Kabupaten Bandung.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian :
1. Teridentifikasinya potensi masya-rakat Desa Langensari KecamatanLembang Kabupaten Bandung.
2. Teridentifikasinya peran serta masyarakatdalam pemanfaatan potensi yang ada dimasyarakat Desa Langensari
Manfaat penelitian :
1. Mengembangkan pengetahuan tentangpotensi yang dimiliki masyarakat.
2. Memberikan masukan kepada PemerintahPusat, Pemerintah Propinsi dan PemerintahKota/Kabupaten mengenai pentingnyaperan serta masyarakat di dalammelakukan pembangunan desa yangberkesinambungan.
D. Metode Penelitian
Pendekatan dan metode penelitian yangdigunakan bersifat eksploratif. Eksploratif yangdimaksud disini adalah mencari dan menggalipersepsi yang ada dan berkembang dimasyarakat dengan menggali kenyataan sosialyang ada dan mengkaitkannya denganbudaya yang dimiliki oleh anggota masyarakat.
Teknik pengumpulan data yang digunakanadalah wawancara, observasi dan studidokumentasi.
Lokasi dalam penelitian ini adalah DesaLangensari, Kecamatan Lembang, KabupatenBandung.
E. Kajian Pustaka
Manusia sebagai mahkluk sosial yangsecara tidak langsung menjadi anggotamasyarakat dalam perjalanan kehidupannyaakan selalu dihadapkan pada berbagaimacam masalah yang melingkupi dirinya.Masalah yang ada biasanya berupa hal-halyang berkenaan dengan hambatan-hambatandalam pencapaian tujuan untuk pemenuhankebutuhan hidup. Segala kebutuhan tersebutpada dasarnya tidak dapat dipenuhi tanpaharus menggunakan pengetahuannya dandalam rangka penggunaan pengetahuantersebut kadangkala manusia mengalamihambatan-hambatan yang tidak dapatdipecahkan dengan pengetahuan yangdimilikinya atau keterbatasan pengetahuanyang ada pada dirinya sehingga men-jadikannya sebagai masalah sosial.
Pada umumnya, permasalahan sosial yangterjadi di masyarakat bukan hanya akibat dariadanya penyimpangan perilaku atau masalahkepribadian. Namun juga sebagai akibat daripermasalahan struktural, kebijakan yang keliru,implementasi kebijakan yang tidak konsistendan tidak adanya partisipasi atau peran sertadari masyarakat dalam membangunlingkungannya. Pembangunan yang diikutidengan menumbuhkan peran serta masyarakatmampu mengangkat untuk memberikan tempatnyata pada katalis pembangunan (agent ofdevelopment). Menurut Edi Suharto (2005)masyarakat adalah sekelompok orang yangmemiliki perasaan yang sama atau menyatusatu-sama lain karena mereka saling berbagiidentitas kepentingan-kepentingan yang sama,perasaan memiliki, dan biasanya berada padasatu tempat atau lokasi yang sama. Sedangkanpartisipasi atau peranserta adalah keterlibatanmasyarakat dalam pembangunan diri,kehidupan dan lingkungan mereka (BrithaMikkelsen, 2001). Menurut Carry J. Lee dalamJusman Ikandar (1993) ada 3 (tiga) asumsi nilaiperan serta, yaitu : (1) setiap warga masyarakatharus berperan serta secara aktif di dalamupaya perubahan masyarakat; (2) peran sertawarga masyarakat haruslah seluas mungkin;dan (3) peran serta warga masyarakat itu harusdilaksanakan melalui organisasi-organisasiyang demokratis.
74
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 73-80
Pada dasarnya setiap masyarakatmempunyai mekanisme untuk mengatasimasalah kesejahteraan sosial yang terjadi padamasyarakat tersebut. Potensi untuk mengatasimasalah kesejahteraan sosial yang ada padasetiap masyarakat dalam bentuk sumber dayaalam, sumber daya manusia serta sumber dayasosial dan budaya. Untuk mempertahankankehidupannya, masyarakat memanfaatkan danmengorganisasikan semua sumber daya yangada, dalam berbagai aktivitas ekonomi, politik,keagamaan, kesenian, gotong royong,dan sebagainya. Pemanfaatan dan peng-organisasian aktivitas inilah yang diistilahkansebagai lembaga atau institusi sosial.Masyarakat lokal, dan lembaga sosialnya,mengorganisasir diri untuk mengelola sumberdaya alam dan sumber daya manusia yangada dalam masyarakat untuk memenuhikebutuhannya.
Tetapi dalam kenyataannya, masyarakatdesa masih sulit untuk melakukan hal tersebutdi atas karena mereka dililit berbagaiketerbatasan, bukan saja modal tetapi jugapengetahuan dan keterampilan. Selain itu jugabelenggu adat dan kebiasaan yang ada,seringkali kurang menguntungkan dilihat darisegi kepentingan pembangunan. Selain itu juga,diantara masyarakat desa masih ada yangbelum menyadari kemampuan dirinya sendiri,sehingga mereka lebih banyak bergantungkepada orang lain atau pihak lain.
Dalam hubungannya dengan masalahkesejahteraan sosial, masyarakat desamempunyai beragam lembaga untukmengatasi masalah tersebut. Ada lembagasosial yang berfungsi untuk mengatasi masalahkemiskinan, ada pula lembaga lain yangberfungsi untuk masalah moralitas. Daripemikiran ini diambil kesimpulan bahwa setiapmasyarakat mempunyai potensi untuk mengatasimasalah kesejahteraan sosial yang ada secaramandiri (self help).
I I . HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Desa Langensari adalah salah satu desayang berada di Kecamatan LembangKabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat,dengan luas wilayah 468,12 Ha. Jumlahpenduduk Desa Langensari sebanyak 9.932 jiwa
yang terdiri dari 4.951 jiwa laki-laki dan 4.981jiwa perempuan, dan terdapat 2.779 kepalakeluarga (KK) (data tahun 2004). Penduduk usiaproduktif (15-45 tahun) berjumlah 4.920 jiwa.
Desa Langensari terletak pada jalurpegunungan di sebelah utara kota Bandung.Perbatasan Desa Langensari yaitu sebelah utaraDesa Cikole, Desa Cikidang dan Desa Cibogo;sebelah selatan Desa Mekarwangi; sebelahbarat Desa Pagarwangi dan Desa Kayuambon;dan di sebelah timur Desa Wangunharja.Orbitasi (jarak antara waktu tempuh dari desake kota kecamatan) kurang lebih 3 Km denganjarak tempuh sekitar 10 menit. Selain itu, DesaLangensari merupakan salah satu jalan menujuke obyek wisata Maribaya dan penakaranlebah. Hal ini memungkinkan Desa Langensaritidak sepi dari banyaknya wisata lokal, nasionalmaupun internasional yang berkunjung ke obyekwisata Maribaya tersebut.
Desa Langensari yang berada padabentang wilayah berbukit dengan suhu rata-rataharian 17 – 22 derajat celcius sangatlah cocokuntuk daerah pertanian, terutama untuk produksihasil pertanian kubis, kentang, tomat, ubi kayu,padi ladang, dan jagung. Memperhatikankondisi alam yang demikian hampir 39,7%penduduk bekerja sebagai petani dan 21,2%sebagai buruh tani.
Disamping bidang pertanian, masyarakatDesa Langensari juga bekerja pada bidangpeternakan antara lain sebagai peternak ayam,sapi, kambing, kuda dan penangkaran buaya.
Kesadaran dari lembaga pemerintahan diDesa Langensari terhadap pentingnyapendidikan bagi warga masyarakatnyasangatlah tinggi. Hal ini terlihat dengan jumlahbangunan sekolah yang ada dan layak pakaiyaitu Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 2buah, SD/sederajat sebanyak 4 buah, dan SLTPsebanyak 1 (satu) buah. Sedangkan untukgedung SLTA tidak ada. Hal ini menyebabkanjumlah lulusan SLTA di Desa Langensari sangatrendah yaitu hanya 0,09%.
Memperhatikan ketersediaan saranapendidikan yang ada, memungkinkanmasyarakat untuk mengenyam tingkatpendidikan seperti yang dianjurkan olehpemerintah yaitu wajib belajar 9 tahun. Tetapipada kenyataannya, tingkat kesadaranterhadap pendidikan bagi masyarakat Desa
75
Pemanfaatan Potensi Masyarakat Di Desa Langensari, Kec. Lembang, Bandung (Ivo Noviana)
Langensari masih rendah. Hal ini terlihat daritingginya jumlah penduduk yang hanya tamatSekolah Dasar (SD)/sederajat yaitu 71,16% dantamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/sederajat sebanyak 16,15%. Melihat kondisi ini,pada dasarnya orang tua memandang anaksebagai aset yang dapat membantuperekonomian keluarga karena nilai anak lebihdipentingkan sebagai tenaga kerja produktif.Sehingga pendidikan anak kurang mendapatperhatian (paling tinggi sekelas SD), inidikarenakan anak lebih difokuskan untukbekerja baik sebagai buruh bangunan, buruhtani, dan sebagainya. Hal ini menunjukkanbelum adanya kesadaran dari masyarakatDesa Langensari terhadap pentingnyapendidikan bagi masa depan anak mereka.
Data Pemerintah Kabupaten Bandungtahun 2004 tentang Desa Langensarimenggambarkan berbagai permasalahansosial. Menurut data formal, permasalahankesejahteraan sosial yang ada, masalah fakirmiskin/keluarga miskin yang paling menonjolyaitu sekitar 67,58% dibanding masalah sosiallainnya. Akibat dari kemiskinan tersebutmenyebabkan rendahnya kesadaran masya-rakat akan tingkat pendidikan, dimana sekitar71,16% hanya tamat Sekolah Dasar (SD).
B. Potensi Masyarakat
Semangat gotong royong, kebersamaan,maupun tolong menolong masih dapatdijumpai pada masyarakat perdesaan. Hal inijuga masih dijumpai pada masyarakat DesaLangensari. Kepedulian dan gotong royongyang ada pada masyarakat Desa Langensaritidak hanya pada saat kerja bakti menjagakebersihan dan keamanan desa atau padasaat pembangunan jalan/jembatan, tetapijuga kepedulian dalam membantu wargamasyarakat yang kurang mampu. Misalnya sajaada warga masyarakat yang menjadi orangtua asuh bagi warga yang tidak mampu dalammenyekolahkan anaknya atau kepedulianterhadap warga yang sedang ditimpa musibahseperti kematian atau ketika ada warga yangsakit.
Dalam penanganan masalah kesejah-teraan sosial di Desa Langensari sangat pentingmemperhatikan peran serta masyarakatsetempat, yang diwujudkan melalui berbagai
lembaga kemasyarakatan yang tumbuh danberkembang di tengah masyarakat. Beragamlembaga kemasyarakatan yang terdapat diDesa Langensari dalam kaitan denganpenanganan masalah kesejahteraan sosialantara lain :
a. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Kegiatan Pembinaan KesejahteraanKeluarga (PKK) di Desa Langensari di bagi kedalam 4 (empat) kelompok kerja (Pokja), yaitu:
- POKJA I : bidang pendidikan dankeagamaan
- POKJA II : bidang pemberdayaanperempuan
- POKJA III : bidang lingkungan hidupdan kemasyarakatan
- POKJA IV : bidang kesehatan
POKJA I, untuk bidang pendidikandilakukan pembinaan bagi remaja putri yangputus sekolah dalam bentuk penyuluhan yangdilakukan sebulan sekali. Sedangkan dalambidang keagamaan kegiatan yang dilakukanantara lain kegiatan mengaji dan ceramahkeagamaan. Dalam setiap pertemuan, anggotapengajian mengumpulkan dana sebesar Rp.500,-/orang yang digunakan untuk perawatanatau renovasi masjid/mushola dan pemberianbantuan kepada fakir miskin.
POKJA II, untuk bidang pemberdayaanperempuan menekankan kepada pengem-bangan usaha seperti home industry bagi ibu-ibu rumah tangga. Salah satu home industryyang berkembang di RW 04 adalah pembuatankue kering dan kue basah.
POKJA III, untuk bidang lingkungan hidup,pemanfaatan lahan kosong di depan/belakang rumah menjadi apotek hidup, dimanahasilnya berguna bagi pemilik dan masyarakatyang membutuhkan. Untuk bidang ke-masyarakatan dilaksanakan melalui kerjasamadengan pokja-pokja lain, kegiatannya adalahpenyuluhan terhadap masyarakat.
POKJA IV, untuk bidang kesehatan antaralain meliputi posyandu yang dilakukan setiapsebulan sekali dan Keluarga Berencana (KB).
76
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 73-80
Kegiatan PKK selain diatur dalamKelompok Kerja (Pokja), juga terdapat berbagaimacam kegiatan lainnya yang dimanfaatkanuntuk menangani permasalahan sosial, yaitu :
1. Jimpitan
Kegiatan ini merupakan upayamengumpulkan dana berupa uang sebesarRp. 1.000,-/bulan dari setiap kepalakeluarga (KK) pada minggu pertama (setiaptanggal 5 tiap bulannya). Dana inidigunakan sebagai bantuan untuk wargayang mengalami musibah (seperti sakit dankematian). Besarnya dana bantuan yangdiberikan untuk warga yang sakit sebesar Rp.20.000,- sampai Rp. 25.000,-. Sedangkanjika dirawat di rumah sakit dana bantuanyang diberikan sebesar Rp. 50.000,-. Untukdana bantuan kematian sebesar Rp.150.000,- bagi keluarga yang ditinggalkan.
Dalam jimpitan ini, warga diharap-kan kerelaannya untuk menyumbang,dalam arti tidak ada paksaan bagi wargayang tidak menyumbang pada saatpengambilan dana jimpitan.
2. Arisan
Kelompok arisan dibentuk hampir ditingkat RW dan desa. Biasanya arisandilakukan sebulan sekali. Dalam arisan inidilakukan pengumpulan dana untuk mengisikas RW dari setiap pembayar arisan Rp.10.000,- diambil Rp. 2.000,- yangdimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatansosial, pembangunan desa dan administrasiRW.
b. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa(LKMD)
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa(LKMD) adalah organisasi lokal yangdiharapkan dapat memotori kegiatan-kegiatanpembangunan desa. Tetapi pada ke-nyataannya, kegiatan yang dilakukan LKMD diDesa Langensari hanya berupa pengajian untukkaum pria dan kegiatan dalam pembangunandan perenovasian masjid.
c. Karang Taruna
Karang Taruna merupakan organisasi desayang mempunyai kegiatan antara lain :kegiatan olah raga dan kesenian, melakukankegiatan sensus (seperti : sensus sosial, sensusekonomi, dan sensus penduduk) serta kegiatankeagamaan. Kegiatan tersebut, disampinguntuk meningkatkan kesehatan dan prestasiremaja, juga bermanfaat untuk membantupemerintah desa dalam memperbaharui datapermasalahan kesejahteraan sosial dan potensidana kesejahteraan sosial.
Sesuai dengan struktur organisasikepengurusan Karang Taruna digambarkansebagai berikut : Ketua Umum dibantu olehKetua I dan II, Sekretaris I dan II, serta beberapaseksi yaitu kerohanian, seksi pendidikan danlatihan, seksi pengabdian masyarakat, seksilingkungan hidup, seksi pelayanan kesejah-teraan sosial, seksi kesenian, seksi hubunganmayarakat, serta seksi usaha. Dalam per-jalanannya, Karang Taruna di Desa Langensaribelum banyak melakukan kegiatan kesejah-teraan sosial sebagaimana tergambar dalamuraian kepengurusan diatas. Walaupundemikian, Karang Taruna sudah ikut berperandalam rangka mengisi kegiatan remaja di DesaLangensari.
I I I. PERAN SERTA MASYARAKAT
TERHADAP POTENSI YANG ADA
Potensi yang dimiliki oleh masyarakatDesa Langensari untuk membangun desanyasangat besar, baik berupa organisasimasyarakat atau lembaga sosial yang adamaupun masih besarnya rasa kesetiakawanan,kepedulian dan gotong royong. Tetapi, daripotensi yang ada tersebut belum sepenuhnyadidayagunakan, khususnya melalui keikut-sertaan atau adanya peran serta dari masya-rakat untuk membangun. Hal ini tentunya me-nyebabkan potensi yang ada tidak tergali dantidak dapat dimanfaatkan sebagaimanamestinya.
Namun, seperti umumnya masyarakatdesa di dalam tata hidupnya yang bersifat ”selfcentered” artinya masyarakat desa di dalam
77
Pemanfaatan Potensi Masyarakat Di Desa Langensari, Kec. Lembang, Bandung (Ivo Noviana)
menata kehidupannya memusatkan per-hatiannya pada kepentingannya sendiri danuntuk memecahkan masalah-masalah yangdihadapinya cenderung untuk mendasarkanpemikirannya pada pengalaman didalamkehidupannya sendiri. Selain itu, berbagaikelemahan yang dimiliki oleh masyarakat desadan perlu mendapatkan perhatian adalahkurangnya kesadaran akan pendidikan formaldan pengetahuan umum sehingga meng-akibatkan minimnya pengetahuan masyarakatdesa untuk mengembangkan dan menciptakanpandangan yang menjangkau ke masa depan.Tidak adanya keberanian dari masyarakat desauntuk mengambil resiko inovasi dan lebih kuatmempertahankan kebiasaan yang dialaminyasejak lama juga menjadikan kendala bagipengembangan dan pembangunan masya-rakat desa. Begitu juga yang terjadi padamasyarakat Desa Langensari, dimana merekamelihat bahwa pendidikan formal tidaklahpenting bagi mereka, karena sebagian besardari tenaga kerja produktif yang ada hanyatamat SD/sederajat. Mereka pada umumnyamelihat dari kebiasaan orang tua mereka,bahwa dengan pendidikan yang rendah ataumungkin sama sekali tidak bersekolah, dapatbertahan hidup dan menghidupi keluargamereka walau hanya sebagai petani atau buruhtani.
Kuatnya birokrasi di pemerintahan desa,serta tebalnya sifat paternalistik tidak menjaminefektifnya pengorganisasian potensi desa untukmembangun. Budaya ”rembug desa” perludikembangkan lagi, dan untuk mewujudkanperanan dan keterlibatan masyarakat desadidalam membangun desanya, adanyapranata Lembaga Musyawarah Desa (LMD)yang memutuskan dan membahas pem-bangunan desa dan diharapkan dari wakil-wakil masyarakat yang terlibat didalamnyadapat mengembangkan potensi dan semangatdesa, termasuk prakarsa desa untuk meng-gerakkan desanya sendiri. Desa Langensarisudah mempunyai organisasi lokal yang cukupbaik, antara lain PKK, LKMD dan KarangTaruna. Tetapi dalam perjalanananya, dua daritiga organisasi lokal (LKMD dan Karang Taruna)yang ada, yang diharapkan dapatmengembangkan dan membangun desa tidakberjalan sebagaimana mestinya. Untuk PKK,walaupun banyak kegiatan yang dilakukan baikoleh ibu-ibu maupun remaja puteri, terutama
remaja puteri yang putus sekolah, tetapi dalamperkembangan selanjutnya mereka kekurangantenaga penggerak dalam hal ini tenaga kader(indigenous worker). Peranan kader sangatlahpenting, karena dengan adanya kaderdiharapkan dapat menggantikan perananpetugas pembangunan desa dalammelanjutkan kegiatan-kegiatan pembangunandesa. Kader adalah orang-orang yang berasaldari masyarakat setempat yang dengansukarela bersedia ikutserta dalam pelaksanaanberbagai kegiatan dalam program pem-bangunan desa. Keengganan masyarakatLangensari untuk terlibat sebagai kader adalahkarena ketidakpercayaan diri mereka akibatrendahnya tingkat pendidikan yang merekamiliki. Dengan keterbatasan pengetahuan yangada, mereka merasa tidak mampu untukmelakukan tugas yang dibebankan padamereka.
Ketiadaan regenerasi dalam halpengkaderan juga berlaku di LKMD danKarang Taruna. Seharusnya, kedua organisasilokal tersebut dapat menggerakkan danmemberikan semangat kepada wargamasyarakat dengan kegiatan-kegiatan yangpositif tetapi pada kenyataannya hanyamelakukan hal-hal yang bersifat insidental.Karang Taruna misalnya hanya terlibat ketikamelakukan sensus penduduk. Begitu juga LKMDyang diharapkan dapat memotori setiapkegiatan di Desa Langensari tidak berjalandengan semestinya. Yang ada adalah kegiatanLKMD hanya membangun atau merenovasimesjid. Sama seperti yang terjadi di PKK,ketiadaan pengkaderan di 2 (dua) organisasilokal ini menyebabkan organisasi ini tidakdapat berjalan sesuai fungsinya.
Namun sebenarnya ada perbedaan yangmendasar antara ketiadaan pengkaderan diPKK dengan Karang Taruna dan LKMD.Jika di PKK kurangnya pengkaderan karenaketidakpercayaan diri dari warga masya-rakatnya. Di Karang Taruna dan LKMDketiadaan pengkaderan ini terjadi karena wargamasyarakat malas untuk membangun kembalikedua organisasi lokal tersebut yang sudah”vakum” atau kurang adanya kegiatan. Bagimereka, sangatlah sulit untuk melanjutkan suatuorganisasi yang sudah ”tidur” tersebut.
Melihat organisasi lokal yang ada di DesaLangensari, maka patut dipertimbangkan
78
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 73-80
adalah untuk memfungsikan lembaga-lembaga yang ada (dalam hal ini PKK, LKMDdan Karang Taruna) untuk dapat secara lebihbaik mengantisipasi pogram-programpembangunan. Oleh karena itu, makasebaiknya dilakukan program-programpelatihan bagi warga Desa Langensari denganmenggunakan peran serta (partisipasi) darimasyarakat yang berlandaskan pada prinsipkebutuhan hidup. Pelatihan (training) ini perludiberikan terlebih dahulu kepada masyarakatsebelum mereka melakukan program pem-bangunan yang diberikan oleh ahli-ahli dariluar desa. Pelatihan tersebut dapat berupapeningkatan pengetahuan maupun keteram-pilan/keahlian terhadap perkembanganteknologi yang semakin berkembang. Dengandiikutsertakannya tenaga setempat dalampelatihan, maka kepercayaan masyarakat ataskemampuannya sendiri bertambah besar,sehingga rasa tanggung jawab terhadap pro-gram pembangunan desa bertambah kuat.
IV. PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Setiap masyarakat mempunyai meka-nisme untuk mengatasi permasalahankesejahteraan sosial yang terdapat didalamnya dalam bentuk potensi masya-
rakat. Potensi tersebut dalam bentuksumber daya alam, sumber daya manusiaserta sumber daya sosial dan budaya.
2. Pemanfaatan terhadap potensi dansumber yang ada di dalam masyarakatdapat dilakukan dengan adanya peranserta dari masyarakat, sehingga dapatdilakukan secara optimal.
3. Peranan dari lembaga lokal (PKK, KarangTaruna, dan sebagainya) yang ada sangatpenting untung menggerakkan masya-rakat agar berperan aktif didalammemajukan desanya.
B. Rekomendasi
1. Matinya suatu lembaga tergantung darisumber daya manusia yang me-ngelolanya. Oleh karena itu perlu adanyakaderisasi terhadap lembaga-lembagalokal yang ada sehingga dapat ber-kembang untuk menunjang pembangunandesa.
2. Perlu adanya program-program pelatihan(training) untuk masyarakat desa yangbertujuan untuk meningkatkan kemampuandan keterampilan sehingga mereka dapatmengolah dan memanfaatkan potensi dansumber daya yang ada.
DAFTAR PUSTAKA
Adi, Isbandi Rukminto, 2003, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas:Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis, Jakarta; Lembaga Penerbit Fakultas EkonomiUniversitas Indonesia.
Adimihardja, Kusnaka & Harry Hikmat, 2003, Participatory Research Appraisal dalam Pengabdian danPemberdayaan Masyarakat, Bandung; Humaniora Utama Press.
Jayaputra, Achmadi, 2005, Kendala Perkembangan Potensi Masyarakat (Studi Kasus di KelurahanKawatuna, Kota Palu), dalam Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha KesejahteraanSosial, Volume 10 No. 1 April 2005, Jakarta; Puslit PKS Balatbangsos Departemen Sosial RI.
Mikkelsen, Britha, 2001, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan, Jakarta;Yayasan Obor Indonesia.
Suharto, Edi, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis PembangunanKesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung; Refika Aditama.
79
Pemanfaatan Potensi Masyarakat Di Desa Langensari, Kec. Lembang, Bandung (Ivo Noviana)
Suparlan, Parsudi, 1994, Pembangunan yang Terpadu dan Berkesinambungan, Jakarta; BalatbangsosDepartemen Sosial RI.
Rudito, Bambang, 2005, Masalah Sosial Penyebab Kemiskinan, dalam Indonesian Journal for Sustain-able Future, Volume 1 No. 1 Juli 2005, Jakarta; ICSD.
BIODATA PENULIS :
Ivo Noviana, alumnus Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan IlmuKesejahteraan Sosial tahun 1998, Kini sebagai staff bidang Kerjasama dan Publikasi Pusat Penelitiandan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial,Departemen Sosial RI.
80
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 01, 2006 : 73-80