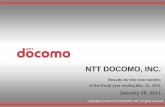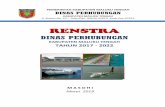ISLAM DI MALUKU, NTT, DAN PAPUA
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of ISLAM DI MALUKU, NTT, DAN PAPUA
ISLAM DI PAPUA, MALUKU, DAN NTT
Disusun Oleh:Adne Lativa Azham Minervani (01)Hanif Mufadlilah (11)Laila Nauvi Rachma (12)Adam Adhe Nugraha (26)
Islam di Papua Pendahuluan
Dari sumber-sumber Barat diperoleh catatan bahwa pada abad ke XVI sejumlah daerah di Papua bagian barat, yakni wilayah-wilayah Waigeo, Missool, Waigama, dan Salawati tunduk kepada kekuasaan Sultan Bacan di Maluku. Berdasarkan cerita populer dari masyarakat Islam Sorong dan Fakfak, agama Islam masuk di Papua sekitar abad ke 15 yang dilalui oleh pedagang–pedagang muslim. Perdagangan antara lain dilakukan oleh para pedagang–pedagang suku Bugis melalui Banda (Maluku Tengah) dan oleh para pedagang Arab dari Ambon yang melalui Seram Timur.
7 Teori Teori Papua
Teori ini merupakan pandangan adat dan legenda yang melekat di sebagaian rakyat asli Papua, khususnya yang berdiam di wilayah fakfak, kaimana, manokwari dan raja ampat (sorong). Teori ini memandang Islam bukanlah berasal dari luar Papua dan bukan di bawa dan disebarkan oleh kerejaan ternate dan tidore atau pedagang muslim dan da’I dari Arab, Sumatera, Jawa, maupun Sulawesi.
Namun Islam berasal dari Papua itu sendiri sejak pulau Papua diciptakan oleh Allah Swt. mereka juga mengatak bahwa agama Islam telah terdapat di Papua bersamaan dengan adanya pulau Papua sendiri, dan mereka meyakini kisah bahwa dahulu tempat turunya nabi adam dan hawa berada di daratan Papua.
Teori AcehStudi sejarah masukanya Islam di Fakfak yang dibentuk
oleh pemerintah kabupaten Fakfak pada tahun 2006, menyimpulkan bahwa Islam datang pada tanggal 8 Agustus 1360 M, yang ditandai dengan hadirnya mubaligh Abdul Ghafar asal Aceh di Fatagar Lama, kampong Rumbati Fakfak.
Teori Arab
Menurut sejarah lisan Fakfak, bahwa agama Islam mulai diperkenalkan di tanah Papua, yaitu pertamakali di Wilayah jazirah onin (Patimunin-Fakfak) oleh seorang sufi bernama Syarif Muaz al-Qathan dengan gelar Syekh Jubah Biru dari negeri Arab, yang di perkirakan terjadi pada abad pertengahan abad XVI, sesuai bukti adanya Masjid Tunasgain yang berumur sekitat 400 tahun atau di bangun sekitar tahun 1587.
Teori JawaBerdasarkan catatan keluarga Abdullah Arfan pada tanggal 15 Juni 1946, menceritakan bahwa orang Papua yang pertama masuk Islam adalah Kalawen yang kemudian menikah dengan siti hawa farouk yakni seorang mublighat asal Cirebon. Kalawen setelah masuk Islam berganti nama menjadi Bayajid, diperkirakan peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1600. Jika dilihat dari silsilah keluarga tersebut, maka Kalawen merupakan nenek moyang dari keluarga Arfan yang pertama masuk Islam.
Teori BandaMenurut Halwany Michrob bahwa Islamisasi di Papua, khusunya di Fakfak dikembagkan oleh pedagang-pedagang Bugis melalui banda yang diteruskan ke Fakfak melalui seram timur oleh seorang pedagang dari Arab bernama haweten attamimi yang telah lama menetap di Ambon
Teori BacanMenurut Arnold, raja bacan yang pertama masuk Islam bernama zainal abiding yang memerintah tahun 1521 M, telah menguasai suku-suku di Papua serta pulau-pulau disebelah barat lautnya, seperti waigeo, misool, waigama dan salawati. Kemudian sultan bacan meluaskan kekuasaannya sampai ke semenanjung onin fakfak, di barat laut Papua pada tahun 1606 M, melalui pengaruhnya dan para pedagang muslim maka para pemuka masyarakat pulau – pulau tadi memeluk agama Islam. Meskipun masyarakat pedalaman masih tetap menganut animisme, tetapi rakyat pesisir menganut agama Islam.
Teori Maluku Utara (Ternate-Tidore)Dalam sebuah catatan sejarah kesultanan Tidore yang menyebutkan bahwa pada tahun 1443 M Sultan Ibnu Mansur ( Sultan Tidore X atau sultan Papua I ) memimpin ekspedisi ke daratan tanah besar ( Papua ). Setelah tiba di wilayah pulau Misool, raja ampat, maka sultan ibnu Mansur mengangkat Kaicil Patrawar putra sultan Bacan dengan gelar Komalo Gurabesi ( Kapita Gurabesi ). Kapita Gurabesi kemudian di kawinkan dengan putri sultan Ibnu Mansur bernama Boki Tayyibah. Kemudian berdiri empat kerajaan dikepulauan Raja Ampat tersebut adalah kerajaan Salawati, kerajaan Misool/kerajaan Sailolof, kerajaan Batanta dan kerajaan Waigeo. Dari Arab, Aceh, Jawa, Bugis, Makasar, Buton, Banda, Seram, Goram, dan lain – lain.
Bukti-bukti 1. terdapat living monument yang berupa makanan Islam yang
dikenal dimasa lampau yang masih bertahan sampai hari ini di daerah Papua kuno di desa Saonek, Lapintol, dan Beo di distrik Waigeo.
2. tradisi lisan masih tetap terjaga sampai hari ini yang berupa cerita dari mulut ke mulut tentang kehadiran Islam di Bumi Cendrawasih.
3. Naskah-naskah dari masa Raja Ampat dan teks kuno lainnya yang berada di beberapa masjid kuno.
4. Di Fakfak, Papua Barat dapat ditemukan delapan manuskrip kuno berhuruf Arab. Lima manuskrip berbentuk kitab dengan ukuran yang berbeda-beda, yang terbesar berukuran kurang lebih 50 x 40 cm, yang berupa mushaf Al Quran yang ditulis dengan tulisan tangan di atas kulit kayu dan dirangkai menjadi kitab. Sedangkan keempat kitab lainnya, yang salah satunya bersampul kulit rusa, merupakan kitab hadits, ilmu tauhid, dan kumpulan doa
Nowadays Karena sasaran pertama Islam hanya tertuju kepada soal
keimanan dan kebenaran tauhid saja, oleh karena itu pada masa dahulu perkembangan Islam sangatlah lamban selain dikarnakan pada saat itu tidak generasi penerus untuk terus mengeksiskan Islam di pulau Papua, dan merekapun tiadak memiliki wadah yang bias menampungnya.
Namun perkembangan Islam di Papua mulai berjalan marak dan dinamis sejak irian jaya berintegrasi ke Indonesia, pada saat ini mulai muncul pergerakan dakwah Islam, berbagai institusi atau individu-individu penduduk Papua sendiri atau yang berasal dari luar Papua yang telah mendorong proses penyebaran Islam yang cepat di seluruh kota-kota di Papua. Hadir pula organisasi keagamaan Islam di Papua, seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, LDII<dan pesantren-pesantren dengan tradisi ahlussunah waljama’ah.
Islam di Maluku Teori Masuknya Islam
Menurut Abdul Kadir G. Goro dalam sebuah thesisnya yang berjudul “Sejarah Perkembangan Agama Islam di Kabupaten Kupang” (1977), Sejarah masuknya agama Islam di Kupang erat hubungannya dengan penyebaran agama Islam di Indonesia. Dari Ternate, Islam meluas meliputi pulau-pulau di seluruh Maluku, dan juga daerah pantai timur Sulawesi.
Seorang peneliti dan penulis buku tentang sejarah Islam di NTT, Munandjar Widiyatmika di Kupang, Selasa mengatakan bahwa “Dari sumber-sumber sejarah yang berhasil saya himpun, agama Islam masuk pertama kali di pulau Solor di Menanga pada abat ke-15 kemudian ke Ende dan Alor,” katanya dalam suatu wawancara terkait masuknya agama Islam pertama di NTT.
Proses Masuknya Islam
Maluku sebagai daerah kepulauan merupakan daerah yang subur terkenal sebagai penghasil rempah terbesar. Untuk itu sebagai dampaknya banyak pedagangpedagang yang datang ke Maluku untuk membeli rempah-rempah tersebut. Di antara pedagang-pedagang tersebut terdapat pedagang-pedagang yang sudah memeluk Islam sehingga secara tidak langsung Islam masuk ke Maluku melalui perdagangan dan selanjutnya Islam disebarkan oleh para mubaligh salah satunya dari Jawa
.
Kerajaan Ternate Kerajaan Gapi atau yang kemudian lebih dikenal sebagai Kesultanan
Ternate (mengikuti nama ibukotanya) Didirikan oleh Baab Mashur Malamo pada 1257. Kesultanan Ternate
memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-17. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke -16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Di masa jaya kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi utara, timur dan tengah, bagian selatan kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik.
Pulau Gapi (kini Ternate) mulai ramai di awal abad ke-13, penduduk Ternate awal merupakan warga eksodus dari Halmahera. Awalnya di Ternate terdapat 4 kampung yang masing – masing dikepalai oleh seorang momole (kepala marga), merekalah yang pertama – tama mengadakan hubungan dengan para pedagang yang datang dari segala penjuru mencari rempah – rempah
Penduduk Ternate semakin heterogen dengan bermukimnya pedagang Arab, Jawa, Melayu dan Tionghoa.
Tahun 1257 momole Ciko pemimpin Sampalu terpilih dan diangkat sebagai Kolano (raja) pertama dengan gelar Baab Mashur Malamo (1257-1272). Kerajaan Gapi berpusat di kampung Ternate, yang dalam perkembangan selanjutnya semakin besar dan ramai sehingga oleh penduduk disebut juga sebagai “Gam Lamo” atau kampung besar (belakangan orang menyebut Gam Lamo dengan Gamalama). Semakin besar dan populernya Kota Ternate, sehingga kemudian orang lebih suka mengatakan kerajaan Ternate daripada kerajaan Gapi.
Tak ada sumber yang jelas mengenai kapan awal kedatangan Islam di Maluku khususnya Ternate. Namun diperkirakan sejak awal berdirinya kerajaan Ternate masyarakat Ternate telah mengenal Islam mengingat banyaknya pedagang Arab yang telah bermukim di Ternate kala itu. Beberapa raja awal Ternate sudah menggunakan nama bernuansa Islam namun kepastian mereka maupun keluarga kerajaan memeluk Islam masih diperdebatkan. Hanya dapat dipastikan bahwa keluarga kerajaan Ternate resmi memeluk Islam pertengahan abad ke-15.
Portugal Tahun 1512 Portugal untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Ternate dibawah pimpinan Fransisco Serrao, atas persetujuan sultan, Portugal diizinkan mendirikan pos dagang di Ternate. Portugal datang bukan semata–mata untuk berdagang melainkan untuk menguasai perdagangan rempah–rempah, pala dan cengkih di maka Maluku ditalkukkan. Sultan Bayanullah wafat meninggalkan pewaris-pewaris yang masih sangat belia. Akibatnya, terjadi perebutan kekuasaan antar pangeran. Portugal memanfaatkan kesempatan ini dan mengadu domba keduanya hingga pecah perang saudara. Kubu permaisuri Nukila didukung Tidore sedangkan pangeran Taruwese didukung Portugal. Setelah meraih kemenangan pangeran Taruwese justru dikhianati dan dibunuh Portugal. Tak ingin menjadi Malaka kedua yang telah dikalahkan Portugal, sultan Khairun mengobarkan perang pengusiran Portugal. Secara licik gubernur Portugal, Lopez de Mosquita mengundang Sultan Khairun ke meja perundingan dan akhirnya dengan kejam membunuh sultan yang datang tanpa pengawalnya. Berkobarlah semangat seluruh Maluku untuk mengusir Potugal. Portugal pun dikalahkan, namun Ternate mulai melemah, Kerajaan Portugal yang telah bersatu dengan Portugal pada tahun 1580 mencoba menguasai kembali Maluku dengan menyerang Ternate.
1). Kompleks Istana, Masjid dan Makam Kesultanan Ternate Istana Kesultanan Ternate bergaya bangunan abad XIX,
berlantai dua, menghadap ke arah laut, dikelilingi perbentengan terletak satu kompleks dengan masjid Jami’ Ternate, secara administratif terletak di Soa-Siu, Kelurahan Letter C, Kodya Ternate, Kabupaten Maluku Utara. Istana ini telah dipugar pada tahun anggaran 1978/1979-1981/1982 oleh Mendikbud Dr. Daoed Joesoef. Istana tersebut kini dialih fungsikan sebagai museum Kesultanan Ternate.9 Istana ini dikelilingi oleh perbentengan yang kini masih nampak sisa-sisa pondasinya.
Masjid jami’ Kesultanan Ternate juga terletak di kompleks istana, berdenah persegi, mengahadap ke timur, memiliki satu ruang utama beratap susun 7 tingkat. Masjid yang didirikan Sultan Hamzah ini berukuran 22.40 x 39.30 m dengan tinggi keseluruhan 21.74 m
2). Kompleks Makam di Bukit Foramadyahe Tokoh penting yang dimakamkan di kompleks ini, adalah Sultan
Khairun dan Sultan Baabullah, yang baik jirat dan nisannya tidak berhias.
3). Koleksi museum Kesultanan Ternate Museum kesultanan merupakan bekas dari istana yang dialih
fungsikan, di dalam museum ini menyimpan koleksi artefak atau relief yang berkaitan dengan eksistensi Kesultanan Ternate. Hasil penelitian tahun 1995, mengidentifikasi koleksi museum sebagai berikut.
Warisan Ternate
KelompokNomor Jenis Artefak
Ideofak 1 Al Quran2 Tempat berdoa1 Bendera atau panji-panji2 Singgasana/mahkota dll.3 Tongkat kebesaran1 Pedang/tombak/senapan2 Topi militer3 Baju besi4 Tameng/perisai
Sultan Ternate Daftar Sultan Ternate Berikut merupakan daftar nama Sultan Ternate:[1]
Kaicil Mashur Malamo atau Kaicili Tsyuka (1257-1277) Kaicil Jamin atau Cili Kadarat (1277-1284) Kaicil Kamalu atau Abu Sahid (1284-1298) Kaicil Bakuku (1298-1304) Kaicil Nagarah Malamo (1304-1317) Kaicil Patsarangah Malamo (1317-1322) Kaicil Sidang Arif Malamo (1322-1331) Kaicil Paji Malamo (1331-1332) Kaicil Sah Alam (1332-1343) Kaicil Tulu Malamo (1343-1347) Kaicil Kie Mabiji (1347-1350) Kaicil Ngolo Macayah (1350-1357) Kaicil Mamole (1357-1359) Kaicil Gapi Malamo (1359-1372) Kaicil Gapi Baguna atau Gapi Baguna I (1372-1377) Kaicil Kamalu (1377-1432) Kaicil Sia atau Gapi Baguna II (1432-1465) Kaicil Gapi Baguna atau Marhum (1465-1486)
Kerajaan TidoreMenurut kisahnya, di daerah Tidore ini sering terjadi pertikaian antar para Momole (kepala
suku), yang didukung oleh anggota komunitasnya masing-masing dalam
memperebutkan wilayah kekuasaan persukuan. Pertikaian tersebut seringkali menimbulkan pertumpahan darah. Usaha untuk mengatasi pertikaian tersebut selalu mengalami
kegagalan.
Menurut catatan Kesultanan Tidore, kerajaan ini berdiri sejak Jou Kolano Sahjati naik tahta pada 12 Rabiul Awal 502 H (1108 M). Namun, sumber tersebut tidak menjelaskan secara jelas lokasi pusat kerajaan pada saat itu. Asal usul Sahjati bisa dirunut dari kisah kedatangan Djafar Noh dari negeri Maghribi di Tidore. Noh kemudian mempersunting seorang gadis setempat, bernama Siti Nursafa. Dari perkawinan tersebut, lahir empat orang putra dan empat orang putri. Empat putra tersebut adalah: Sahjati, pendiri kerajaan Tidore; Darajati, pendiri kesultanan Moti; Kaicil Buka, pendiri kesultanan Makian; Bab Mansur Malamo, pendiri kesultanan Ternate. Sedangkan empat orang putri adalah: Boki Saharnawi, yang menurunkan raja-raja Banggai; Boki Sadarnawi, yang menurunkan raja-raja Tobungku; Boki Sagarnawi, yang menurunkan raja-raja Loloda; dan Boki Cita Dewi, yang menurunkan Marsaoli dan Mardike. Kerajaan Tidore merupakan salah satu pilar yang membentuk Kie Raha, yang lainnya adalah Ternate, Makian dan Moti.
Pada tahun 1495 M, Sultan Ciriliyati naik tahta dan menjadi penguasa Tidore pertama yang memakai gelar sultan. Saat itu, pusat kerajaan berada di Gam Tina. Ketika Sultan Mansur naik tahta tahun 1512 M, ia memindahkan pusat kerajaan dengan mendirikan perkampungan baru di Rum Tidore Utara. Posisi ibukota baru ini berdekatan dengan Ternate, dan diapit oleh Tanjung Mafugogo dan pulau Maitara. Dengan keadaan laut yang indah dan tenang, lokasi ibukota baru ini cepat berkembang dan menjadi pelabuhan yang ramai.
Dalam sejarahnya, terjadi beberapa kali perpindahan ibukota karena sebab yang beraneka ragam. Pada tahun 1600 M, ibukota dipindahkan oleh Sultan Mole Majimo (Alauddin Syah) ke Toloa di selatan Tidore. Perpindahan ini disebabkan meruncingnya hubungan dengan Ternate, sementara posisi ibukota sangat dekat, sehingga sangat rawan mendapat serangan. Pendapat lain menambahkan bahwa, perpindahan didorong oleh keinginan untuk berdakwah membina komunitas Kolano Tomabanga yang masih animis agar memeluk Islam. Perpindahan ibukota yang terakhir adalah ke Limau Timore di masa Sultan Saifudin (Jou Kota). Limau Timore ini kemudian berganti nama menjadi Soasio hingga saat ini.
Perlawanan Pada abad ke 16 M, orang Portugis dan Spanyol datang ke
Maluku –termasuk Tidore– untuk mencari rempah-rempah, momonopoli perdagangan kemudian menguasai dan menjajah negeri kepulauan tersebut. Dalam usaha untuk mempertahankan diri, telah terjadi beberapa kali pertempuran antara kerajaaan-kerajaan di Kepulauan Maluku melawan kolonial Portugis dan Spanyol. Terkadang, Tidore, Ternate, Bacan dan Jailolo bersekutu sehingga kolonial Eropa tersebut mengalami kesulitan untuk menaklukkan Tidore dan kerajaan lainnya.
Sepeninggal Portugis, datang Belanda ke Tidore dengan tujuan yang sama. Sultan yang dikenal paling gigih dan sukses melawan Belanda adalah Sultan Nuku (1738-1805 M). Selama bertahun-tahun, ia berjuang untuk mengusir Belanda dari seluruh kepulauan Maluku, termasuk Ternate, Bacan dan Jailolo. Perjuangan tersebut membuahkan hasil dengan menyerahnya Belanda pada Sultan Nuku pada 21 Juni 1801 M.
Silsilah Dari sejak awal berdirinya hingga saat ini, telah berkuasa 38 orang sultan di Tidore. Saat ini, yang berkuasa adalah Sultan Hi. Djafar Syah. (nama dan silsilah para sultan lainnya, dari awal hingga yang ke-37 masih dalam proses pengumpulan data).
Pemerintahan Kerajaan Tidore berdiri sejak 1108 M dan berdiri sebagai kerajaan merdeka hingga akhir abad ke-18 M. setelah itu, kerajaan Tidore berada dalam kekuasaan kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, Tidore menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kekuasaan Wilayah sekitar pulau Tidore yang menjadi bagian wilayahnya adalah Papua, gugusan pulau-pulau Raja Ampat dan pulau Seram.
Di Kepulauan Pasifik, kekuasaan Tidore mencakup Mikronesia, Kepulauan Marianas, Marshal, Ngulu, Kepulauan Kapita Gamrange, Melanesia, Kepulauan Solomon dan beberapa pulau yang masih menggunakan identitas Nuku, seperti Nuku Haifa, Nuku Oro, Nuku Maboro dan Nuku Nau.
Wilayah lainnya yang termasuk dalam kekuasaan Tidore adalah Haiti dan Kepulauan Nuku Lae-lae, Nuku Fetau, Nuku Wange dan Nuku Nono.
Sistem Pemerintahan Struktur tertinggi kekuasaan berada di tangan sultan. Seleksi
sultan dilakukan melalui mekanisme seleksi calon-calon yang diajukan dari Dano-dano Folaraha (wakil-wakil marga dari Folaraha), yang terdiri dari Fola Yade, Fola Ake Sahu, Fola Rum dan Fola Bagus. Dari nama-nama ini, kemudian dipilih satu di antaranya untuk menjadi sultan.
Sosial BudayaMasyarakat di Kesultanan Tidore merupakan penganut agama Islam
yang taat, dan Tidore sendiri telah menjadi pusat pengembangan agama Islam di kawasan kepulauan timur Indonesia sejak dulu kala.
Karena kuatnya pengaruh agama Islam dalam kehidupan mereka, maka para ulama memiliki status dan peran yang penting di masyarakat. Kuatnya relasi antara masyarakat Tidore dengan Islam tersimbol dalam ungkapan adat mereka: Adat ge mauri Syara, Syara mauri Kitabullah (Adat bersendi Syara, Syara bersendi Kitabullah). Perpaduan ini berlangsung harmonis hingga saat ini
Islam di NTT
Menurut beberapa sumber, agama Islam pertama kali memasuki Nusa Tenggara Timur pada abad ke-15 yang dibawa oleh para pedagang dan ulama tepatnya di Pulau Solor, Flores Timur. Penyebaran agama Islam ini pertama kali
dilakukan seorang ulama pedagang dari Palembang yang bernama Syahbudin bin Salman Al Faris yang kemudian dikenal dengan sebutan
Sultan Menanga. Mengenai pola pendekatan penyebar agama Islam di NTT asal Palembang Syahbudin bin Salman Al Faris menggunakan pendekatan kekeluargaan dan memegang
tokoh-tokoh kunci daerah setempat.
Kerajaan GowaKesultanan Gowa atau kadang ditulis Goa, adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari Suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Wilayah kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Gowa dan beberapa bagian daerah sekitarnya. Kerajaan ini memiliki raja yang paling terkenal bergelar Sultan Hasanuddin, yang saat itu melakukan peperangan yang dikenal dengan Perang Makassar terhadap VOC yang dibantu oleh Kerajaan Bone yang dikuasai oleh satu wangsa Suku Bugis dengan rajanya Arung Palakka. Perang Makassar bukanlah perang antarsuku karena pihak Gowa memiliki sekutu dari kalangan Bugis; demikian pula pihak Belanda-Bone memiliki sekutu orang Makassar. Perang Makassar adalah perang terbesar VOC yang pernah dilakukannya pada abad ke-17.
Pengislaman Penerimaan Islam pada beberapa tempat di Nusantara
memperlihatkan dua pola yang berbeda. Pertama, Islam diterima oleh masyarakat bawah, kemudiaan berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas disebut bottom up. Kedua, Islam diterima langsung oleh elite penguasa kerajaan kemudian disosialisasikan dan berkembang pada lapisan masyarakat bawah disebut top down.
Penerimaan Islam di Gowa menurut penulis sejarah Islam, memperlihatkan pola yang kedua. Kerajaan yang mula-mula memeluk Islam dengan resmi di Sulawesi Selatan adalah kerajaan kembar Gowa-Tallo.
Tanggal peresmian Islam itu menurut lontara Gowa dan Tallo adalah malam Jum’at, 22 September 1605, atau 9 Jumadil Awal 1014 H. Dinyatakan bahwa Mangkubumi kerajaan Gowa / Raja Tallo I Mallingkaeng Daeng Manyonri mula-mula menerima dan mengucapkan kalimat Syahadat (Ia di beri gelar Sultan Abdullah Awwalul Islam) dan sesudah itu barulah raja Gowa ke-14 Mangenrangi Daeng Manrabia (Sultan Alauddin). Dua tahun kemudian seluruh rakyat Gowa-Tallo memeluk agama Islam berdasar atas prinsip cocius region eius religio, dengan diadakannya shalat Jumat pertama di masjid Tallo tanggal 9 November 1607 / 19 Rajab 1016 H.
Zaman KeemasanSetelah Kerajaan Gowa menerima Islam, semakin menapak
puncak kejayaannya. Pada masa pemerintahan Raja Gowa XV I Manuntungi Daeng Mattola Karaeng Ujung Karaeng Lakiung Sultan Malikulsaid (1639-1653), kekuasaan dan pengaruhnya kian meluas dan diakui sebagai pemegang hegemoni dan supremasi di Sulawesi Selatan, bahkan kawasan Timur Indonesia.
Kemashuran Sultan Malikulsaid sampai ke Eropa dan Asia, terutama karena pada masa pemerintahannya, dia ditunjang oleh jasa-jasa Karaeng Pattingalloang sebagai Mangkubuminya yang terkenal itu, baik dari segi sosok kecendiakawanannya maupun keahliannya dalam berdiplomasi. Tidak heran, Gowa ketika itu telah mampu menjalin hubungan internasional yang akrab dengan raja-raja dan pembesar dari negara luar, seperti Raja Inggris, Raja Kastilia di Spanyol, Raja Portugis, Raja Muda Portugis di Gowa (India), Gubernur Spayol dan Marchente di Mesoliputan (India), Mufti Besar Arabia dan terlebih lagi dengan kerajaan-kerajaan di sekitar Nusantara.
Hubungan Internasional
Kerjasama dengan bangsa-bangsa asing, terutama Eropa sejak Somba Opu menjadi Bandar Niaga Internasional. Bangsa Eropa gemar dengan rempah-rempah telah menjalin hubungan dagang dengan Gowa, seperti Inggris, Denmark, Portugis, Spanyol, Arab, dan Melayu.
Mereka telah mendirikan kantor perwakilan dagang di Somba Opu. Dari tahun ke tahun hubungan Kerajaan Gowa dengan bangsa Eropa tidak mengalami ronrongan. Barulah terganggu setelah kehadiran orang-orang Belanda yang ingin memonopoli perdagangan dan menjajah.
Peperangan April 1655 armada Gowa yang langsung dipimpin Hasanuddin
menyerang Buton, dan berhasil mendudukinya serta menewaskan semua tentara Belanda di negeri itu.
Setelah Belanda melihat kenyataan peperangan di Kawasan Timur Nusantara banyak menimbulkan kerugian menghadapi Gowa. Belanda dengan berbagai siasat menawarkan perdamaian. Tahun 1655 Belanda mengutus Willem Vanderbeck bersama Choja Sulaeman menghadap Sultan membawa pesan damai dari Gubernur jenderal Joan Maectsuyker tetapi tidak berhasil. Tanggal 17 Agustus 1655 tercapai perjanjian perdamaian 26 pasal sebagai hasil perundingan antara utusan Gowa yang diwakili Karaeng Popo dengan Gubernur Jenderal Belanda yang diwakili Dewan Hindia, Van Oudshoon. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Panglima perang Belanda Mayor Van Dam di Batavia.
Perjanjian itu kemudian oleh Sultan dianggap sangat merugikan Gowa, terutama atas pasal larangan orang-orang Makassar berdagang di Banda dan Ambon, maka Gowa akhirnya menolak perjanjian itu. Tanggal 20 November 1655 utusan Gubernur Jenderal Joan Maetsyuiker untuk sekian kalinya mencoba lagi menawarkan perdamaian dengan mengutus van Wesenhager, tetapi Gowa menolaknya karena tuntutannya merugikan Gowa. Demikian berbagai siasat perdamaian yang diajukan Belanda selalu gagal sehingga permusuhan tidak terelakkan, sehingga terjadi pertempuran poun terus bergolak antara Gowa dengan Belanda, mulai dari perairan Maluku, Banda sampai Makassar.
Kemundunran Peperangan demi peperangan melawan Belanda dan bangsanya sendiri (Bone) yang dialami Gowa, membuat banyak kerugian. Kerugian itu sedikit banyaknya membawa pengaruh terhadap perekonomian Gowa. Sejak kekalahan Gowa dengan Belanda terutama setelah hancurnya benteng Somba Opu, maka sejak itu pula keagungan Gowa yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya akhirnya mengalami kemunduran. Akibat perjanjian Bongaya, pada tahun 1667 sultan Hasanuddin Tunduk. Dalam perjanjian itu, nyatalah kekalahan Makassar.
Sultan-sultan Tumanurunga (+ 1300) Tumassalangga Baraya Puang Loe Lembang I Tuniatabanri Karampang ri Gowa Tunatangka Lopi (+ 1400) Batara Gowa Tuminanga ri Paralakkenna Pakere Tau Tunijallo ri Passukki Daeng Matanre Karaeng Tumapa'risi' Kallonna (awal abad
ke-16) I Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiyung Tunipallangga
Ulaweng (1456-1565) I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibatte I Manggorai Daeng Mameta Karaeng Bontolangkasa Tunijallo
(1565-1590) I Tepukaraeng Daeng Parabbung Tuni Pasulu (1593). I Mangari Daeng Manrabbia Sultan Alauddin Tuminanga ri
GaukannaBerkuasa mulai tahun 1593 - wafat tanggal 15 Juni 1693. Merupakan penguasa Gowa pertama yang memeluk agama Islam.
I Mannuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiyung Sultan Malikussaid Tuminanga ri Papang Batuna
I Mappasomba Daeng Nguraga Sultan Amir Hamzah Tuminanga ri Allu'I Mallawakkang Daeng Mattinri Karaeng Kanjilo Tuminanga ri
Passiringanna Sultan Mohammad Ali (Karaeng Bisei) Tumenanga ri Jakattara I Mappadulu Daeng Mattimung Karaeng Sanrobone Sultan Abdul Jalil
Tuminanga ri Lakiyung. La Pareppa Tosappe Wali Sultan Ismail Tuminanga ri Somba Opu I Mappaurangi Sultan Sirajuddin Tuminang ri Pasi I Manrabbia Sultan Najamuddin I Mappaurangi Sultan Sirajuddin Tuminang ri Pasi. (Menjabat untuk
kedua kalinya pada tahun I Mallawagau Sultan Abdul Chair I Mappibabasa Sultan Abdul Kudus Amas Madina Batara Gowa I Mallisujawa Daeng Riboko Arungmampu Tuminanga ri Tompobalang I Temmassongeng Karaeng Katanka Sultan Zainuddin Tuminanga ri
Mattanging ( I Manawari Karaeng Bontolangkasa I Mappatunru / I Mangijarang Karaeng Lembang Parang Tuminang ri
Katangka La Oddanriu Karaeng Katangka Tuminanga ri Suangga
I Kumala Karaeng Lembang Parang Sultan Abdul Kadir Moh Aidid Tuminanga ri Kakuasanna
I Malingkaan Daeng Nyonri Karaeng Katangka Sultan Idris Tuminanga ri Kalabbiranna
I Makkulau Daeng Serang Karaeng Lembangparang Sultan Husain Tuminang ri Bundu'na
I Mangimangi Daeng Matutu Karaeng Bonto Nompo Sultan Muhammad Tahur Muhibuddin Tuminanga ri Sungguminasa
Andi Ijo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Kadir Aidudin (1946-1960) merupakan Raja Gowa terakhir.
Penyebaran Pada abad ke-16 muncul Kerajaan Gowa yang
berasal dari Sulawesi selatan. Pengislaman dari Jawa disini tidak begitu berhasil, akan tetapi berkat usaha seorang ulama asal Minangkabau pada awal abad ke-17, raja Gowa itu akhirnya memeluk agama Islam juga. Nah, atas kegiatan orang-orang Bugis, maka Islam masuk pula di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara, juga beberapa pulau di Nusa Tenggara.
Dengan meluasnya kekuasaan Kerajaan Tallo dan Goa di Nusa Tenggara Timur, maka masuklah agama Islam di Nusa Tenggara Timur. Selain pengaruh dari Sulawesi Selatan, masuknya agama Islam di NTT disebabkan pula oleh masuknya orang-orang yang beragama Islam dari Ternate – Maluku ke daerah ini.
Menurut cerita rakyat di Pulau Alor, pembawa agama Islam yang pertama ke Pulau Alor adalah “Djou Gogo”, Kima Gogo, Salema Gogo, Iyang Gogo, Abdullah dan Muchtar yang berasal dari Ternate-Maluku.
Setelah masuknya agama Islam ke Pulau Solor sekitar abad ke XVI, maka dengan perantaraan orang-orang yang beragama Islam dari Solor, agama Islam masuk ke Batu Besi Kupang sekitar tahun 1613.
Melalui komunikasi laut, agama Islam berhasil dikembangkan di daerah-daerah pesisir Kabupaten Kupang yang strategis letaknya, sehingga terbentuknya masyarakat Islam di Kupang pada mulanya terjadi di daerah-daerah pesisir.