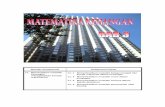IKN - STANDAR
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of IKN - STANDAR
ISSN : 2827-9867
Tokoh
MENANAM STANDAR KOTA HUTAN DI IBU KOTA NEGARA NUSANTARA
IKN
Standar Perencanaan Pembangunan Wilayah Berbasis Ekosistem Hutan Tropis Mendukung Pembangunan IKN
Menggagas Ide Miniatur Hutan Dipterokarpa Ibu Kota Negara Nusantara
Pekerjaan Rumah Dari Pertemuan UNEA 5.2
Integrasi Pembangunan Ibu Kota Negara Baru dan Daerah Penyangganya
Mewujudkan Pembangunan IKN Rendah Karbon melalui Penerapan Prinsip Bangunan Ramah Lingkungan & Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan
Green Computing, Strategi TIK Ramah Lingkungan di Ibu Kota Negara
Dalam mendukung kelestarian lingkungan, pembangunan IKN didasarkan pada prinsip mendesain sesuai kondisi alam dan rendah emisi karbon. Terdapat KPI khusus yang mendukung pembangunan IKN sebagai kota dunia apabila ditinjau melalui bidang LHK yaitu menargetkan 75% kawasan hijau di wilayah IKN.
Dr. Nur Hygiawati RahayuSafeguard Lingkungan “Kota Dunia untuk Semua”
Vol. 1 No. 2, Maret 2022
Daftar IsiSenarai Kepala BSILHK
Fokus Kebijakan
Pekerjaan Rumah dari Pertemuan UNEA 5.2
1
Standardisasi LHK
Menggagas Ide Miniatur Hutan Dipterokarpa Ibu Kota Negara Nusantara
5
Standar Perencanaan Pembangunan Wilayah Berbasis Ekosistem Hutan Tropis Mendukung Pembangunan IKN
17
Mewujudkan Pembangunan IKN Rendah Karbon melalui Penerapan Prinsip Bangunan Ramah Lingkungan & Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan
22
Ide & OpiniIntegrasi Pembangunan Ibu Kota Negara Baru dan Daerah Penyangganya
27
Darma Penyuluhanan Kehutanan Menyongsong Era Standardisasi
33
Urgensi Kaji Ulang Regulasi Baku Mutu Timbal (Pb)
38
Green Computing, Strategi TIK Ramah Lingkungan di Ibu Kota Negara
43
Merentas Jalan Penguatan Literasi Bersama Perpustakaan BPSILHK Solo
47Alamat Sekretariat RedaksiMajalah STANDAR: Better Standar Better Living
Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHKJl. Gunung Batu No.5 Bogor 16618, Jawa BaratE-mail : [email protected] : majalah.bsilhk.menlhk.go.id
Vol. 1 No.2, Maret 2022
TokohDr. Nur Hygiawati Rahayu
Safeguard Lingkungan “Kota Dunia untuk Semua”
52
Cerita TapakPotret Penerapan Standar Instrumen Karhutla
57
Penerbit:
Badan Standardisasi Instrumen LHKKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan2022
Majalah STANDAR: Better Standar Better Living terbit 6 kali dalam setahun (Januari, Maret, Mei, Juli, September, November).
Pembina : Kepala BSILHK
Penanggung Jawab : Sekretaris BSILHK
Pemimpin Redaksi : Yayuk Siswiyanti
Redaktur Pelaksana/Editor :
Dyah PuspasariTutik SriyatiLusi S. GinogaRattah H. H
Sekretariat Redaksi:
Indah Rahmawati
Desain Grafis :
Suhardi Mardiansyah
Tim Redaksi
ii
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
Senarai
Connecting Global People for Better Standard Better Living Recover Together Recover Stronger
iii
Tabik,
Adalah semangat yang saat ini sedang digaungkan Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK). Terhubung secara global untuk aksi mengawal lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui perumusan dan penerapan standar. Kolaborasi antar negara untuk mencari peluang perbaikan dan jalan keluar permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan secara bersama-sama melalui forum diplomasi internasional. Recover Together Recover Stronger.
Beberapa pertemuan diplomasi telah diikuti BSILHK pada bulan Maret tahun 2022 ini, yaitu Pertemuan Majelis Lingkungan PBB–UNEA (United Nations Environment Assembly) 5.2. dan Konvensi Minamata COP4. BSILHK juga berpartisipasi dalam pre-COP4 side event dengan menyelenggarakan webinar. Webinar Engaging the ASGM and Coal Energy Sector Towards a Mercury-Free Indonesia. Beberapa agenda sedang dijajaki untuk keterlibatan BSILHK pada side event G20 Indonesia 2022, World Mangrove Center, pertemuan teknis Steering Committee The Korea Indonesia Forest Corporation Center (KIFC), juga penjajagan dengan organisiasi internasional ISO. Pertemuan global tersebut diikuti BSILHK dalam kerangka menyuarakan pentingnya standar instrumen dalam safeguard lingkungan.
Dalam konteks safeguard lingkungan, BSILHK juga terlibat dalam mengawal pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) dalam konsep forest city. Pembangunan IKN secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kondisi lingkungan hidup dan tutupan kawasan hutan yang beriringan dengan kegiatan yang dilakukan. Untuk mendukung pembangunan IKN dengan tetap mempertahankan kondisi lingkungan hidup dan tutupan kawasan hutan diperlukan standar instrumen baik dalam proses pra konstruksi, pembangunan kontruksi maupun pengelolaannya kedepan.
Majalah Standar: Better Standard Better Living Vol I No 2 bulan Maret 2022 mengangkat tema “Menanam Standar Kota Hutan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara”.
Tentu topik tersebut menarik untuk disimak sebab mengintegrasikan konsep modernitas tanpa mengusik kelestarian lingkungan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.
Terdapat beragam artikel pada edisi ini yang memperkaya sudut pandang pembaca tentang konsep forest city di IKN Nusantara tersebut. Penjelasan gamblang Dr. Nur Hygiawati Rahayu, Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas, tentang IKN Nusantara sebagai embrio “Kota Dunia untuk Semua” dan strategi dalam pengendalian lingkungan dan tutupan kawasan hutan, pada kolom tokoh membuka cakrawala pengetahuan kita.
Narasi tersebut diperkaya beragam artikel terkait yang ditulis dari beragam perspektif baik dari aspek ekologis melalui pengembangan miniatur hutan kota dipterokarpa, pembangunan rendah emisi karbon, dan aspek teknologi melalui desain green computing untuk infrastruktur IKN serta aspek perencanaan wilayah melalui identifikasi kebutuhan standar perencanaan pembangunan IKN dan integrasi wilayah IKN dengan penyangganya. Tak kalah pentingnya adalah urgensi standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan yang dibutuhkan oleh otoritas pengembanan IKN untuk mengawal terwujudnya konsep forest city tersebut.
Membumikan standar dan instrumen lingkungan hidup dan kehutanan guna mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia tak kalah menantangnya. Terdapat beberapa hal yang menggelitik yang dibahas pada kolom opini. Di antaranya adalah urgensi untuk mengkaji ulang batas aman polutan timbal. Dimana regulasi yang ada belum mampu mengimbangi dinamika perubahan yang terjadi. Selanjutnya,
iv
Presiden Jokowi berada di Ibu Kota Baru. Sumber: www.minews.id
darma penyuluh kehutanan menyongsong era standarisasi tak boleh dianggap enteng, sebab penyuluh akan menjadi garda terdepan diseminasi standar.
Geliat Badan Standardisasi Instrumen LHK dalam membangun literasi standar tingkat tapak pun mulai terlihat. Balai Penerapan Standar Instrumen LHK (BPSILHK) Solo mulai merintis penguatan literasi bagi masyarakat di sekitar KHDTK Gombong. BPSILHK Banjarbaru pun turut berbagi cerita di tingkat tapak tentang penerapan standar instrumen kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Tentu kiprah unit kerja BSILHK tersebut patut diapresiasi dan menjadi inspirasi dalam diseminasi standar instrumen LHK.
Semoga saat ini maupun kedepan kiprah BSILHK semakin menguat baik dalam tataran nasional maupun global untuk terwujudnya kualitas lingkungan dan hutan yang terkendali.
Selamat Membaca.
Sekretaris Badan
Nur Sumedi
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
FOKUS KEBIJAKAN
1
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
PEKERJAAN RUMAH DARI PERTEMUAN UNEA 5.2
Dyah PuspasariSekretariat Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan KehutananEmail: [email protected]
Sejarah baru kembali ditorehkan Indonesia dalam Pertemuan Majelis Lingkungan PBB (United Nations Environment Assembly,
UNEA) 5.2, Nairobi, awal Maret 2022. Seruan Indonesia untuk mengelola danau secara berkelanjutan melalui rancangan Resolusi Sustainable Lake Management (Resolusi Danau) berhasil disepakati dan diadopsi oleh negara-negara anggota UNEA, Rabu (2/3).
Delegasi Republik Indonesia yang hadir secara in-person dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Laksmi Dhewanthi, didampingi oleh unsur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan KBRI Nairobi. Tim KLHK yang hadir in-person terdiri atas unsur Biro Kerja Sama Luar Negeri, Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove, dan Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK).
Laksmi yang juga sebagai Vice President UNEA 5 menyampaikan bahwa Delegasi Indonesia berjuang keras menembus proses negosiasi yang panjang dan sangat alot karena banyak negara anggota yang memiliki kepentingan masing-masing. Namun demikian, Indonesia berhasil menyatukan persepsi dan mengakomodir berbagai kepentingan negara-negara yang berbeda pandangan untuk mendukung pentingnya Resolusi Danau ini.
Resolusi usulan Indonesia ini merupakan bagian dari upaya mencapai sasaran Sustainable Development Goals (SDGs) butir 6.6 untuk melindungi dan memulihkan ekosistem yang berhubungan dengan air, termasuk danau. Resolusi ini mendorong pelaksanaan perlindungan, konservasi, restorasi, serta pemanfaatan danau secara berkelanjutan. Resolusi ini diharapkan dapat mewujudkan
Resolusi Danau usulan Indonesia berhasil diadopsi dalam Pertemuan UNEA 5.2. Setelahnya, pekerjaan rumah menanti untuk implementasi di tingkat nasional dan global. Melaksanakannya tentu butuh upaya holistik. Lalu, bagaimana peran standar instrumen LHK untuk mendukung implementasi resolusi tersebut?
2
kesehatan ekosistem danau, baik dari kualitas air, erosi dan sedimentasi, hingga keanekaragaman hayati.
Kesepakatan final Resolusi Danau ini diperoleh pada sesi pleno penutupan UNEA 5.2, setelah sebelumnya beberapa elemen telah disepakati pada sesi Open-Ended Meeting of the Committee of Permanent Representatives (OECPR-5.2) dan sesi informal pada akhir pekan. Kesepakatan final dicapai dengan menggunakan agreed language untuk menjembatani isu transboundary lakes menggunakan target SDGs 6.5 terkait integrated water resource management. Target tersebut di dalamnya mencakup kerja sama lintas batas negara dengan pendekatan yang terintegrasi, lintas sektor, kolaboratif dan koordinatif. Isu ini alot dibahas karena menyinggung permasalahan politik lintas negara. Negara anggota yang memiliki concern terkait isu ini antara lain Mesir, Ethiopia, Irak, Argentina dan Chile.
Pada sesi pleno UNEA 5.2 tersebut, Indonesia menyampaikan National Statement, yang disampaikan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, melalui pre-recorded video. Menteri Siti menggarisbawahi beberapa pesan pokok berikut:
1. Komitmen Indonesia pada perlindungan dan restorasi lingkungan melalui eksplorasi pengetahuan dan implementasi kebijakan menjadi aksi di tingkat tapak;
2. Permintaan dukungan untuk menerapkan Pengelolaan Danau Berkelanjutan serta permintaan dukungan UNEP untuk memfasilitasi pengarusutamaan pengelolaan
danau berkelanjutan dalam agenda global dan memperkuat kolaborasi di antara negara-negara anggota; dan
3. Ajakan untuk memperkuat aksi kemitraan global untuk mengatasi tantangan lingkungan global, termasuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara kolektif menuju pemulihan yang berkelanjutan (sustainable recovery).
Selain Resolusi Danau, delegasi Indonesia di Nairobi berhasil memasukkan sejumlah kepentingan Indonesia dalam berbagai sesi termasuk pada resolusi keluaran UNEA 5.2 lainnya. Di antaranya Indonesia memberikan masukan pada resolusi mengenai marine litter and plastic pollution, future of Global Environment Outlook (GEO), dan animal welfare. Termasuk menyampaikan intervensi pada Side Events Sustainable Ocean terkait tindak lanjut resolusi perlindungan lingkungan laut dan upaya-upaya dalam pengarusutamaan isu kelautan di forum internasional..
Pada sesi Ministerial Declaration, Indonesia berhasil memasukan elemen mengenai Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) dan rujukan mengenai pengelolaan ekosistem berkelanjutan termasuk danau, yang selaras dengan resolusi yang diusulkan oleh Pemerintah Indonesia. Termasuk masukan Indonesia pada Deklarasi Politik peringatan 50 tahun berdirinya United Nations Environment Program (UNEP) atau UNEP@50.
Pada sesi Leadership Dialogue bertema Strengthening Actions for Nature to Achieve the
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
3
SDGs, Ketua Delri menyampaikan intervensi Indonesia terkait 1) komitmen Indonesia pada implementasi SDGs; 2) perkembangan hasil dari penguatan kebijakan di sektor kehutanan (sustainable forest management), termasuk Folu Net Sink 2030; 3) perlindungan kawasan laut yang sudah mencapai 28,1 juta ha (86,5%) dan secara optimis dapat tercapai 100% (32,5 juta ha) di 2030, dan 4) Presidensi G20 Indonesia pada 2022.
Pertemuan UNEA 5.2 ini dihadiri oleh 175 United Nations Member States dengan 3.000 delegasi hadir in-person dan 1.500 delegasi hadir secara virtual. Selain hadir in-person, Delegasi Indonesia juga menghadiri secara virtual yang terdiri atas unsur KLHK, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan KBRI Nairobi.
Acara yang berlangsung pada 28 Februari 2022 sampai 2 Maret 2022 dibuka dan ditutup oleh Menteri Lingkungan Hidup Norwegia, Mr. Espen Barth Eide selaku Presiden UNEA 5. Pada sesi penutupan telah diadopsi 14 resolusi, 1 keputusan, 1 Deklarasi Menteri, dan 1 Deklarasi Politik. Deklarasi politik Sidang Khusus UNEA ditujukan untuk memperingati 50 tahun berdirinya UNEP (UNEP @50).
Empat belas resolusi tersebut adalah: 1) Marine Plastic Pollution dan Framework for Addressing Plastic Product Pollution Including Single-Use Plastics; 2) Science-Policy Panel to Support Action on Chemicals; 3) Waste and Pollution; 4) Sound Management of Chemical and Waste; 5) Sustainable Nitrogen Management; 6) Nature-Based Solutions; Biodiversity and Health; 7) Animal Welfare Environment and Sustainable Development Nexus; 8) Sustainable Lake Management; 9) Sustainable and Resilient Infrastructure; 10) Mineral Resource Governance; 11) Green Recovery; 12) Circular Economy; 13) Future of Global Environment Outlook; dan 14) Equitable Geographical Representation and Balance in the UNEP Secretariat.
Pasca-UNEA 5.2Keberhasilan Indonesia mengusung Resolusi Danau dalam Pertemuan Majelis Lingkungan PBB ini adalah langkah awal memperjuangkan pengelolaan danau berkelanjutan di tingkat nasional dan global. Sebagai tindak lanjutnya, Indonesia sebagai pengusul resolusi Sustainable Lake Management perlu melakukan komunikasi intensif dengan UNEP serta menggalang kemitraan dan mobilisasi sumber
daya untuk memastikan agar resolusi tersebut dapat diimplementasikan dan dilaporkan hasil capaiannya pada persidangan UNEA 6.
Laporan Delegasi Indonesia pada UNEA 5.2 menggarisbawahi bahwa hasil-hasil dari UNEA 5.2 perlu ditindaklanjuti pada tingkat nasional dengan tetap memperhatikan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang sedang berjalan. Mengingat pentingnya upaya segera untuk melaksanakan berbagai resolusi UNEA 5, perlu dilaksanakan diseminasi hasil UNEA 5 dan kerjasama lintas kementerian/lembaga dengan melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan.
Pada tingkat global, Indonesia dapat mendorong kolaborasi implementasi berbagai resolusi UNEA, khususnya mengenai sustainable lake management melalui kerangka South-South and Triangular Cooperation (SSTC). Hasil-hasil dari UNEA 5.2 ini juga diharapkan dapat meningkatkan peluang kerjasama di bidang lingkungan hidup, baik regional maupun global.
Standar Instrumen Menjadi PemanduMengimplementasikan Resolusi Sustainable Lake Management atau pengelolaan danau berkelanjutan tentu membutuhkan upaya holistik. Berbagai aspek mulai dari kebijakan, program, kegiatan, perizinan, promosi, sampai monitoring dan evaluasi, termasuk penegakan hukumnya menjadi kesatuan upaya yang berkontribusi pada pencapaian target resolusi. Apalagi jika termasuk transboundary lakes, maka tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks. Lalu, bagaimana peran standar instrumen LHK untuk mendukung implementasi resolusi tersebut?
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK), sebagai lembaga di KLHK yang mendapat mandat mengawal usaha-usaha pemanfaatan SDA yang berimplikasi pada kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan, berkomitmen untuk mendukung implementasi Resolusi Danau tersebut. BSILHK berperan menguatkan safeguard untuk mengendalikan kualitas lingkungan hidup dan hutan tetap terjaga dengan baik.
Sekretaris BSILHK, Nur Sumedi, saat ditemui di ruang kerjanya pasca menghadiri pertemuan UNEA 5.2, menjelaskan bahwa peran standar instrumen LHK sangat penting untuk mendukung tercapainya target Resolusi Danau. Menurutnya, setelah resolusi diadopsi maka langkah selanjutnya adalah menyusun program, rencana aksi, dan tata waktu implementasi resolusi. Standar-standar instrumen LHK sebagai safeguards sangat dibutuhkan untuk memandu implementasinya, baik pada level makro yaitu standar pengelolaan danau berkelanjutan, dan level mikro misalnya standar erosi, kualitas air, dll.
Hal tersebut dilakukan dengan koridor tugas pokok dan fungsi BSILHK menyelenggarakan koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Hal terpenting berikutnya adalah memastikan bahwa standar-standar yang dibangun diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan.
Dalam konteks resolusi yang diusung Indonesia pada Pertemuan UNEA ini, penguatan safeguards lingkungan tentu tidak terbatas pada Resolusi Danau saja. Resolusi yang diusung pada pertemuan UNEA 4 sebelumnya, yakni resolusi konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (SCP), pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan, pelestarian hutan bakau, perlindungan lingkungan laut, dan manajemen terumbu karang secara berkelanjutan, juga menjadi pekerjaan rumah BSILHK untuk menguatkan safeguardsnya. Keberadaan standar instrumen LHK diharapkan mampu mengendalikan kualitas lingkungan hidup dan hutan agar tetap terjaga dengan baik, terutama dalam mendukung implementasi dan mencapai tujuan resolusi
4
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
5
MENGGAGAS IDE MINIATUR HUTAN DIPTEROKARPAIBU KOTA NEGARA NUSANTARA
Muhammad FajriBalai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup Samarinda. Email: [email protected]
Dengan telah disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, maka pemindahan Ibu
kota negara Indonesia yang baru ke wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur telah memiliki dasar hukum dan politik yang kuat. Ibu Kota yang baru ini bernama Nusantara meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 ha dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha.
Dalam proses pembangunan IKN Nusantara, diperkirakan akan menimbulkan beberapa masalah lingkungan. Beberapa permasalahan itu di antaranya adalah ancaman terhadap tata air dan risiko perubahan iklim, ancaman terhadap flora dan fauna, serta ancaman terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut, pemerintah dalam pembangunan IKN Nusantara akan menerapkan konsep smart city dan forest city dimana konsep tersebut sudah tergambarkan dalam desain IKN Nusantara oleh Sibarani Sofian dan tim yaitu konsep Nagara Rimba Nusa. Konsep ini bermaksud untuk menyatukan alam dan teknologi secara berdampingan, sehingga dapat tercipta kota yang baik serta ramah lingkungan. Penerapan konsep forest city akan berbasis pada: 1) pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), 2) jaringan ruang hijau yang terstruktur, 3) perlindungan habitat satwa yang meliputi wilayah habitat dan daerah jelajah satwa liar kunci, 4) kualitas tutupan lahan yang baik dan terevitalisasinya lanskap “Hutan Hujan Tropis”.
Untuk mewujudkan konsep forest city, pemerintah telah meyusun lima Peta Jalan
Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan. Untuk peta jalan yang berhubungan dengan pemulihan tutupan lahan adalah roadmap ke-3 mengenai pemulihan ekosistem hutan hujan tropis dengan program: 1) pemulihan wilayah konservasi Bukit Suharto, 2) pengkayaan dan restorasi bertahap lanskap hutan tanaman, 3) pengkayaan bertahap koridor hijau dan jaringan ruang terbuka hijau publik. Untuk program pengkayaan dan restorasi lanskap hutan tanaman, maka dibutuhkan rencana kegiatan tahap 1 (2020-2024) dengan melaksanakan rehabilitasi terpadu dan pengkayaan vegetasi di eks hutan tanaman, sekitar ± 5.000 ha areal prioritas, dan pada tahap 2 (2025 dan selanjutnya) melakukan kegiatan restorasi ekosistem dengan melakukan pengaturan lanskap dan pengembangan keragaman vegetasi untuk mencegah penyebaran spesies invasif dan meningkatkan kemampuan suksesi alaminya.
Kegiatan pengkayaan dan restorasi hutan hujan tropis harus menggunakan jenis-jenis endemik Kalimantan. Salah satu jenis penting dan dominan di hutan hujan tropis Kalimantan Timur adalah pohon-pohon dari keluarga dipterokarpa. Famili Dipterokarpa (Dipterocarpaceae) adalah simbol keluarga dari hutan hujan tropis Asia Tenggara dan banyak dari hutan kering musiman di benua Asia Selatan dan Tenggara. Keluarga ini merupakan suku tumbuhan yang seluruh anggotanya berupa pohon yang mempunyai peranan penting, baik dari segi ekonomi maupun ekologi. Dari segi ekonomi, sebagian besar jenis dari suku ini merupakan penghasil kayu komersial untuk memenuhi berbagai keperluan.
Pembangunan miniatur hutan dipterokarpa akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara baik secara politik, ekologi, ekonomi, dan sosial. Untuk memewujudkan hal tersebut perlu dilakukan beberapa strategi yaitu; 1) mengikuti strategi khusus untuk lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan KPI (Key Performance Indicator);2) strategi pencarian sumberdaya bibit dan persemaian; 3) strategi penanaman miniatur hutan dipterokarpa pada lanskap IKN Nusantara.
STANDARDISASI LHK
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
Selain itu, beberapa jenis dipterokarpa juga menghasilkan minyak, damar, dan buah yang mempunyai nilai untuk diperdagangkan. Di Kalimantan Timur, jenis-jenis tumbuhan dari suku dipterokarpa merupakan penyusun utama ekosistem hutan hujan tropis. Dari beberapa hasil penelitian di Kalimantan Timur, ada sekitar 8 marga dengan puluhan jenis pohon dipterokarpa. Marga tersebut antara lain Shorea (meranti), Dryobalanops (kapur), Dipterocarpus (keruing), Anisoptera (mersawa), Parashorea (meranti bunga), Cotylelobium (giam), Vatica (resak) dan Hopea (merawan). Dari marga tersebut ada jenis-jenis yang sudah dikenal untuk kegiatan penanaman yaitu Shorea balangeran, S. leprosula, S. parvifolia, S. agamii, S. atrinervosa, S. ovalis, S. pinanga, Dryobalanps aromatic, D. lanceolata, Dipterocarpus borneensis, D. tempehes, Anisoptera costata, Anisoptera polyandra, Parashorea smythiesii, P. malaanonan, Cotylelobium burckii, Vatica javanica, V. oblongifolia, Hopea mengarawan, H. sangal. Jenis-jenis tersebut biasa ditanam untuk rehabilitasi lahan dan hutan (Omon 2006; Adman 2013; Majuakim dan Kitayama 2013; Pratiwi et al. 2014; Susilo 2016; Andriansyah et al. 2019; Fajri 2019). Selain jenis dipterokarpa, dalam ekosistem hutan hujan tropis di Kalimantan Timur terdapat jenis-jenis non dipterokarpa yang cukup dikenal dan bisa dikembangkan seperti ulin (Eusideroxylon zwageri), gaharu (Aquilaria mallacensis), pasak bumi (Eurycoma longifolia Jack), laban (Vitex pubescens Vahl), Fordia splendidissima, Ficus spp., Litsea spp., Macaranga hypoleuca, Syzygium spp., Archidendron microcarpum, Alstonia spp., Cratoxylum sumatranum, Homalanthus populneus, dan Vernonia arborea (Rayan et al. 2010; Adman et al. 2012; Sidiyasa et al. 2013; Pratiwi et al. 2014; Susanty 2015; Fajri 2019).
Tulisan ini akan memberi informasi kepada para pembaca mengenai kondisi calon IKN Nusantara, hutan dipterokarpa, manfaat dari pembangunan miniatur hutan dipterokarpa, strategi dan desain yang dapat digunakan dalam pembangunan miniatur hutan dipterokarpa. Diharapkan dengan adanya tulisan ini bisa memberikan gambaran tentang ide pembangunan miniatur hutan dipterokarpa kepada para pembaca terutama para stakeholder yang berhubungan langsung dengan pembangunan IKN Nusantara.
Kondisi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara
Lokasi utama IKN Nusantara berada pada kawasan Ijin Usaha Pengelolaan Hutan Tanaman
(IUPHT) PT. ITCI Hutani Manunggal (IHM) berdasarkan SK Menhut 184/Kpts-II/1996 dengan luas konsesi 161.127 Ha. PT. IHM berada pada ketinggian 0-800 m dpl. dengan topografi datar (0-8) 29.41%, landai (9-15) 44.93%, agak curam (15-25) 21.80%, curam (26-40) 3.22%, amat curam (>40) 0.64%. Lokasi IKN Nusantara memiliki formasi geologi Pamaluan, formasi Balikpapan, dan formasi Aluvium dengan jenis tanah yang didominasi oleh Podsolik merah kuning. Pada kawasan ini kondisi tanahnya secara umum kurang subur.
Lokasi IKN Nusantara memiliki Tipe iklim B (Schmidt-Ferguson) basah dengan curah hujan 1.998 mm/tahun (paling tinggi pada bulan Desember dan terendah pada bulan Agustus). Pada kawaan ini dilalui DAS Tunan-Mangga, Sub DAS Bongan, dan Sub DAS Mahakam Ilir. Untuk penyusun vegetasi didominasi oleh tanaman pokok Hutan Tanaman Industri (HTI), yaitu Acacia mangium dan Eucalyptus pellita dengan luas 91.887 ha. Sekitar 17.443 ha (10%) dijadikan kawasan lindung yang berisi jenis-jenis dipterokarpa (S. smithiana, S. johorensis, S. parvifolia, Dipterocarpus sp, V. rassak dan non dipterokarpa seperti ulin (E. zwageri), gaharu (A. mallaccensis), laban (V. pubescens), kayu ara (Ficus spp.), mahang (M. hypoleuca), jambu-jambu (Syzygium sp.), kayu arang (Diospyros borneensis), bawang-bawang (Scodocarpus boornensis), gerunggang (Cratoxylum arborescens), dan dara-dara (Knema latifolia) (PT IHM 2019).
Pengertian Hutan Dipterokarpa
Tipe hutan yang paling luas penyebarannya di Kalimantan adalah hutan dataran rendah dipterokarpa atau dikenal juga dengan sebutan hutan pamah dipterocarpa (Lowland Dipterocarp Forest). Tipe hutan ini tumbuh pada tanah podsolik merah kuning pada elevasi 0-1000 m diatas permukaan laut. Kanopi utama hutan mencapai 30-45m dengan tinggi pohon hingga 60m. Disebut hutan Dipterocarpa karena tipe hutan ini didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan dari suku Dipterocarpaceae terutama marga Anisoptera, Balanocarpus, Cotylelobium, Dipterocarpus, Dryobalanops, Hopea, Parashorea, Shorea, Upuna, dan Vatica. Tidak jarang dalam satu lokasi, beberapa jenis Dipterocarpaceae tumbuh bersama-sama dan menguasai kanopi atas (Kartawinata, 2013).
Dipterocarpaceae merupakan pohon penghasil kayu utama dari hutan hujan tropis yang banyak terdapat di Indonesia bagian barat, Malaysia,
6
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
7
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
Brunei, Filipina dan menyebar kearah timur hingga Papua dan Papua Nugini (Fajri, 2009). Di Kalimantan bagian timur penyebarannya didominasi genus Shorea, Hopea, Dryobalanops, Vatica, dan Dipterocarpus.
Sebagian besar jenis-jenis Dipterocarpaceae terdapat pada daerah beriklim basah, kelembaban tinggi, pada ketinggian tempat 0 - 800 m dpl, dan curah hujan diatas 2000 mm/tahun dengan musim kemarau yang pendek. Jenis-jenis Dipterocarpaceae juga sebagian besar tumbuh pada tanah yang kering, bereaksi asam, bersolum dalam dan liat. Pada kondisi tanah yang asam, perakaran jenis tumbuhan Dipterocarpaceae berasosiasi dengan ektomikoriza sehingga mereka dapat bertahan hidup dan berkembang. Meskipun sebagian besar jenis-jenis Dipterocarpaceae menyukai tanah yang kering dan asam, ada juga sebagian kecil yang mampu tumbuh pada tanah dengan kondisi berkapur, berpasir dan gambut. Pada tanah yang berkapur, jenis Dipterocarpaceae yang dapat ditemukan adalah Hopea aptera, H. billitonensis, Shorea guiao, S. harilandii. Pada tanah berpasir antara lain Dipterocarpus aromatica, Shorea stenoptera, S. falcifera, Hopea bacariana, Upuna borneensis dan Cotylolebium malanaxylon. Pada tanah bergambut antara lain Shorea pltycarpa, S. teysmanniana, S. uliginosa, S. albida, S. pachypylla, S. balangeran, Dryobalanops rappa dan Dipterocarpus corieceus (Al Rasyid et al. 1991).
Manfaat Miniatur Hutan Dipterokarpa di IKN Nusantara
Pembangunan miniatur hutan dipterokarpa pada kawasan IKN Nusantara akan memberikan manfaat yang sangat besar baik secara politik, ekologi, ekonomi, dan sosial. Dibidang politik, untuk politik luar negeri kita ketahui bahwa masalah perubahan iklim sekarang sudah menjadi masalah global terutama masalah peningkatan emisi karbon dan naiknya suhu global. Indonesia sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29 % dengan usaha sendiri dan 41 % bantuan dari pihak lain. Dengan adanya pembangunan miniatur hutan hutan dipterokarpa pada kawasan IKN Nusantara, telah menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia mempunyai komitmen yang kuat untuk memperhatikan faktor-faktor lingkungan dalam pembangunan ibu kota yang baru. Hal ini juga akan menepis kekhawatiran di dalam negeri terutama dari pihak pemerhati lingkungan akan dampak dari pembangunan ibu kota yang baru terhadap
masalah lingkungan yang akan muncul. Secara politik, miniatur hutan dipterokarpa ini bisa dijadikan sebagai ikon smart forest city dan menjadi tempat kunjungan utama para kepala negara dan organisasi internasional ketika berkunjung ke IKN Nusantara. Dibidang ekologi, pembangunan miniatur hutan dipterokarpa ini dapat memberikan banyak manfaat seperti sebagai ameliorasi iklim (pengatur mikroklimat), penangkal polusi butir padatan debu, penangkal polusi gas, pengendali silau cahaya, paru-paru IKN Nusantara, penangkal kebisingan, pengendali air limbah, pengendali erosi, penurun stress, pelestarian plasma nutfah, pusat habitat kehidupan (fauna dan flora) liar, pencegahan instrusi air laut, peningkatan keindahan IKN Nusantara, penyimpan dan penyedia air tanah. Dibidang ekonomi, miniatur hutan dipterokarpa ini bisa dijadikan sebagai salah satu pusat wisata alam di IKN Nusantara sehingga dapat menjadi sumber pemasukan bagi negara. Pengelolaannya juga dapat melibatkan para pengusaha Unit Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga dapat membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Dibidang sosial, keberadaan miniatur ekosistem hutan dipterokarpa ini dapat menjadi pusat wisata dan rekreasi yang mempertemukan banyak orang dari berbagai kalangan.
Strategi Pembangunan Miniatur Hutan Dipterokarpa
Dalam pembangunan miniatur hutan dipterokarpa pada kawasan IKN Nusantara perlu disusun beberapa strategi untuk mencapai tujuan pembangunannya. Beberapa strategi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Mengikuti strategi khusus untuk lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan KPI yang menjadi target untuk mendukung pencapaian visi IKN Baru “Kota Berkelas Dunia untuk Semua” dalam dokumen Masteplan IKN yang telah disusun oleh Bappenas (2020).
2. Strategi pencarian sumberdaya bibit dan Persemaian
Strategi untuk mencari lokasi sumberdaya bibit dipterokarpa dan pemanfaatan persemaian yang baik dan berkualitas dalam proses pemeliharaan bibit hingga memenuhi standar bibit yang siap untuk ditanam berdasarkan SNI 8420:2018 mengenai standar bibit tanaman hutan. Dalam SNI 8420:2018, bibit tanaman hutan harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Untuk persyaratan umum, bibit harus
memiliki asal usul benih (harus punya sertifikat asal usul benih dan sertifikat mutu benih), bibit normal (berbatang tunggal dan lurus, bibit sehat bebas dari hama penyakit dan warna daun normal), batang bibit telah berkayu. Untuk persyaratan-persyaratan khusus bibit tanaman hutan berdasarkan hasil pengukuran untuk jenis-jenis dipterokarpa yaitu tinggi bibit ≥ 40 cm, diameter pangkal batang bibit ≥ 3,5 cm, jumlah daun atau LCR ≥ 7.
Sumberdaya Bibit Dipterokarpa PT. ITCI Kartika Utama adalah salah satu pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang secara geografis berada pada kawasan Pegunungan Meratus dan terletak antara 116o17’-117o06’ BT dan 0o20’1o18’ LS, dengan batas areal sebelah barat sungai bongan, sebelah utara sungai Mahakam, sebelah selatan teluk Balikpapan dan PT. Balikpapan Wana Lestari (BWL). Areal kerja PT. ITCIKU termasuk tipe hutan hujan tropika basah. Pohon-pohon yang tumbuh sebagian besar didominasi oleh jenis-jenis Dipterokarpa, terutama jenis Meranti, Kapur, Keruing dan Bengkirai serta jenis pohon non Dipterokarpa. Jenis-jenis dipterokarpa yang ada di kawasan PT. ITCIKU dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 1. Strategi Lingkungan Hidup dan Kehutanan di IKN Berdasarkan Key Performance Indicator (KPI)
No Strategi Deskripsi singkat KPI IKN
1. Dasar pertimbangan lingkungan untuk rencana tata ruang
• Mengindentifikasi kawasan bernilai ekologi tinggi (misalnya hutan lindung, kawasan konservasi) dan biodiversitas (misalnya daerah jelajah satwa)
• Menetapkan peta dasar lingkungan untuk menentukan kawasan yang tidak dapat dibangun dalam rencana tata ruang
> 75% dari kawasan hijau di area seluas KPIKN (misalnya 65% area hijau yang dilindungi dan 10% untuk produksi pangan)
2. Desain kota yang selaras dan terintegrasi dengan alam (termasuk ruang hijau)
Memaksimalkan ruang hijau (misalnya merehabilitasi konsensi kelapa sawit dan pertambangan yang telah habis masa berlakunya) dan mengintegrasikan alam dalam rencana tata kota
> 50% ruang hijau dalam area K-IKN
3. Strategi rendah karbon Mengidentifikasi peluang untuk pengembangan rendah karbon (misalnya pembangkit energi bersih, transportasi umum dan kontruksi)
Net Zero Emission untuk IKN di Tahun 2045 di KPIKN
Sumber: Masterplan IKN Bappenas (2020)Ket : KPI (Key Performance Indicator), IKN : Ibu Kota Negara, KPIKN: Kawasan Pengembangan IKN
Tabel 2. Jenis-jenis dipterokarpa di PT ITCIKU
No Jenis Sebaran1. Dipterocarpus sp. Punggung bukit, datar, tepi sungai2. Dryobalanops lanceolata Burck Tepi sungai, datar, agak datar, punggung bukit dan lereng bukit3. Dryobalanop becarii Dyer Punggung bukit dan lereng bukit4. Hopea beccariana Burck Datar5. Hopea rudiformis P.S. Ashton Tepi sungai6. Hopea sangal Korth Agak datar7 Shorea johorensis Foxw. Punggung bukit, datar, agak datar dan tepi sungai8. Shorea laevis Ridl. Punggung bukit, datar dan agak datar9. Shorea leprosula Miq. Punggung bukit, tepi sungai, datar dan agak datar
10. Shorea parvifolia Dyer Punggung bukit, datar dan agak datar11. Shorea smithiana Sym. Punggung bukit, datar dan agak datar12. Vatica rassak Blume Datar, agak datar, punggung bukit, lereng bukit dan tepi sungai
Sumber: Newman et al. (1999); Sari dan Karmilasanti (2015); PT. IHM (2019)
8
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
9
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
Berdasarkan hasil penelitian Saridan dan Ngatiman (2012) di PT. Balikpapan Forest Industries, yang sekarang berubah nama menjadi PT. Balikpapan Wana Lestari (BWL), terdapat sekitar 27 jenis pohon dipterocarpaceae, yang terdiri dari enam marga yaitu Shorea, Dipterocarpus, Vatica, Hopea, Dryobalanops dan Anisoptera. Jenis-jenis Dipterokarpa ini tumbuh pada ketinggian antara 86 - 421 m dpl. Jenis-jenis dipterokarpa yang ada di kawasan PT. BWL yang juga merupakan bagian dari Pegunungan Meratus dapat dilihat pada Tabel 3.
Kawasan Hutan Lindung Gunung Lumut (HLGL) secara fisiografik terdiri atas dataran berbukit dan perbukitan yang memiliki ketinggian hingga 650 m dpl yang sebagian besar merupakan hutan primer dan terdapat sedikit hutan bekas tebangan. Di kawasan Hutan Lindung Gunung Lumut terdapat sekitar 24 jenis dipterokarpa yang terdiri dari enam marga, yakni Shorea, Dipterocarpus, Vatica, Hopea, Dryobalanops dan Anisoptera. Jenis-jenis dipterokarpa yang ada Kawasan Hutan Lindung Gunung Lumut (HLGL) dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 3. Jenis-Jenis Dipterokarpa di PT. Balikpapan Wana Lestari
No Jenis Sebaran
1. Anisoptera costata Korth • Tepi sungai2. Dipterocarpus cornutus Dyer • Tepi sungai3. Dipterocarpus gracilis Blume • Punggung bukit, lereng bukit dan agak datar4. Dipterocarpus humeratus Sloot. • Agak datar dan tepi sungai5. Dipterocarpus stellatus P.S. Ashton • Agak datar6. Dipterocarpus tempehes Sloot. • Punggung bukit, lereng bukit, datar dan tepi sungai7. Dryobalanops lanceolata Burck • Tepi sungai, datar dan agak datar8. Hopea beccariana Burck • Datar9. Hopea rudiformis P.S. Ashton • Tepi sungai
10. Hopea sangal Korth • Agak datar11. Shorea agami P.S. Ashton • Agak datar12 Shorea johorensis Foxw. • Punggung bukit, lereng bukit, datar
• agak datar dan tepi sungai13. Shorea laevis Ridl. • Punggung bukit, lereng bukit, datar dan agak datar
14. Shorea leprosula Miq. • Tepi sungai, datar, agak datar, lereng bukit dan punggung bukit
15. Shorea macrobalanos P.S. Ashton • Agak datar16. Shorea ovalis Blume • Tepi sungai, datar dan agak datar17. Shorea palembanica Miq. • Punggung bukit dan lereng bukit18. Shorea parvifolia Dyer • Punggung bukit, lereng bukit, datar dan agak datar19. Shorea parvistipulata F. Heim. • Agak datar20. Shorea patoiensis P.S. Ashton • Punggung bukit dan lereng bukit21. Shorea pauciflora King • Agak datar22. Shorea smithiana Sym. • Punggung bukit, lereng bukit, datar dan agak datar
23. Vatica granulata Sloot. • Agak datar24. Vatica oblongifolia Hook.f • Datar, agak datar dan tepi sungai
Sumber: Saridan danNgatiman (2012)
Tabel 4. Jenis-Jenis Dipterokarpa di Hutan Lindung Gunung Lumut
No Jenis Sebaran1. Anisoptera costata Korth • Puncak bukit, lereng bukit2. Dipterocarpus caudiferus Merr • Lereng bukit3. Dipterocarpus gracilis Blume. • Punggung bukit, lereng bukit dan agak datar4. Dipterocarpus humeratus Sloot. • Lereng bukit dan punggung bukit5. Dipterocarpus tempehes Sloot. • Punggung bukit, lereng bukit, datar dan tepi sungai
6. Dryobalanops lanceolata Burck • Tepi sungai, datar, lereng bukit dan punggung bukit7. Hopea cernua Teijsm. & Binn. • Lereng bukit dan punggung bukit 8. Hopea dryobalanoides Miq • Punggung bukit, lereng bukit dan datar9. Hopea mangerawan Miq • Punggung bukit dan lereng bukit
10. Shorea atrinervosa King • Punggung bukit11. Shorea exelliptica Meijer • Punggung bukit dan lereng bukit12. Shorea inappendiculata Burck • Punggung bukit dan lereng bukit13. Shorea johorensis Foxw. • Punggung bukit, lereng bukit, datar dan agak datar dan tepi
sungai14. Shorea laevis Ridl. • Lereng bukit, punggung bukit, datar dan agak datar 15. Shorea leprosula Miq. • Punggung bukit, lereng bukit, tepi sungai, datar dan agak
datar16. Shorea ovalis Blume. • Tepi sungai, datar dan lereng bukit17. Shorea parvifolia Dyer • Punggung bukit, lereng bukit, tepi sungai, datar dan agak
datar18. Shorea parvistipulata F. Heim. • Agak datar dan lereng bukit19. Shorea patoiensis P.S. Ashton • Punggung bukit, lereng bukit dan datar20. Shorea pauciflora King • Agak datar dan lereng bukit21. Shorea smithiana Sym. • Punggung bukit, lereng bukit, datar dan agak datar
22. Vatica sarawakensis Heim. • Punggung bukit dan lereng bukit23. Vatica umbonata (Hk. f) Burck • Tepi sungai24. Vatica odorata (Griff.) Symington • Datar25 Vatica pauciflora King • Lereng bukit
Sumber: Saridan dan Ngatiman (2012)
Gambar 1. Hutan tanaman di kawasan inti IKN
10
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
11
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
KHDTK Labanan merupakan kawasan hutan alam tropis yang ditujukan khusus untuk penelitian dan pengembangan dengan total luas 7.959,10 ha dan berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 64/Menhut-II/2012. Di KHDTK Labanan terdapat 6-7 marga dan 26-29 jenis tumbuhan dari famili dipterokarpa (Saridan 2012; Saridan dan Fajri 2014). Di KHDTK Labanan juga terdapat kebun benih seluas 30 hektar dengan pohon induk jenis Shorea leprosula dan kebun benih seluas 25 hektar dengan pohon induk Dipterocarpus stellatus. Kebun benih ini bisa juga dijadikan sumber bibit dalam rencana pembangunan miniatur hutan hujan tropis dengan jenis dipterokarpa. Secara umum, jenis dipterokarpa yang ada di Kebun Benih KHDTK Labanan, Berau dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Jenis-Jenis Dipterokarpa di Kebun Benih KHDTK Labanan, Berau
No Jenis Habitat
1. Cotylelobium sp. • Punggung bukit dan lereng bukit2. Anisoptera costata Korth • Tepi sungai, punggung bukit dan lereng
bukit3. Dipterocarpus palembanicus Sloot. • Punggung bukit dan lereng bukit4. Dipterocarpus humeratus Sloot. • Agak datar dan tepi sungai5. Dipterocarpus stellatus Vesque • Punggung bukit dan lereng bukit6. Dipterocarpus tempehes Sloot • Punggung bukit, datar dan tepi sungai7. Dryobalanops lanceolata Burck • Tepi sungai, datar dan agak datar8. Hopea pachycarpa (F. Heim) Symington • Datar dan tepi sungai9. Parashorea malaanonan Merr. • Datar, agak datar dan tepi sungai
10. Shorea agami P.S. Ashton • Agak datar11 Shorea beccariana Burck • Punggung bukit dan lereng bukit12. Shorea johorensis Foxw. • Punggung bukit, datar, agak datar dan tepi
sungai13. Shorea laevis Ridl. • Punggung bukit, datar dan agak datar14. Shorea leprosula Miq. • Punggung bukit, tepi sungai, datar dan agak
datar15. Shorea macrophylla (de Vriese) P.S. Ashton • Agak datar, datar dan tepi sungai15. Shorea macroptera Dyer • Punggung bukit dan lereng bukit16. Shorea ovalis Blume • Tepi sungai, datar dan agak datar17. Shorea palembanica Miq. • Punggung bukit18. Shorea parvifolia Dyer • Punggung bukit, datar dan agak datar19. Shorea parvistipulata F. Heim. • Agak datar20. Shorea patoiensis P.S. Ashton • Punggung bukit21. Shorea pinanga Scheff. • Tepi sungai, datar, agak datar dan lereng bukit22. Shorea seminis Sloot. • Tepi sungai23. Shorea smithiana Sym. • Punggung bukit, lereng bukit, datar dan agak
datar24. Shorea pinanga Scheff. • Punggung bukit dan lereng bukit25. Vatica niten King. • Datar, agak datar dan tepi sungai26. Vatica umbonata Burck • Datar, agak datar dan tepi sungai27. Vatica oblongifolia Hook.f • Datar, agak datar dan tepi sungai
Sumber: Newman et al. (1999); Saridan (2012); Saridan dan Fajri (2013); Fajri dan Saridan (2014), Wahyudi & Fajri (2016); Karmilasanti dan Fajri (2020)
Persemaian
Untuk penyiapan bibit dipterokarpa hingga pemeliharaan sampai dengan siap tanam dapat dilakukan di:
a. Persemaian milik PT. ITCI Hutani Manunggal (IHM) di Kabupaten Penajam Paser UtaraPersemaian milik PT. IHM dengan luas sekitar 10 hektar dan kapasitas persemaian kurang lebih 1 juta bibit. Persemaian ini merupakan persemaian modern dengan standar internasional sehingga penyiapan bibit hingga siap tanam dilakukan dengan sangat hati-hati dan profesional. Dimana persemaian ini sangat terintegrasi dari produksi bibit hingga bibit siap tanam, pengolahan media tanam menggunakan mesin pengolah media tanam yang modern, tempat pemeliharaan bibit yang menggunakan green house dengan faktor lingkungannya sangat terukur dan dipantau selalu, penyiraman dilakukan dengan menggunakan nozzle yang diatur dengan sistem control panel sebagai pengendali on/off secara otomatis, sistem irigasi di persemaian dilengkapi dengan saluran air pembuangan.
b. Persemaian Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) di Kabupaten Penajam Paser UtaraPersemaian milik BPDAS ini rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 120 hektar, rencana lokasinya di kawasan Hutan Produksi Mentawir pada areal IUPHHK-HTI PT. Inhutani 1. Selain itu, untuk kapasitas produksi bibit, direncanakan sebesar 15-20 juta bibit per tahun.
c. Persemaian milik Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup (BBPSILH) di Kota SamarindaPersemain BBPSILH memiliki luas sekitar 3.479,34 m2 dengan kapasitas 20 ribu bibit. Meskipun relatif kecil dari sisi luasan, namun persemaian BBPSILH mempunyai koleksi bibit jenis-jenis dipterokarpa endemik Kalimantan yang sekarang mulai terancam punah.
Strategi Penanaman Miniatur Hutan Dipterokarpa pada Lanskap IKN NusantaraAda beberapa skenario metode penanaman yang dapat dilakukan untuk percepatan pencapaian keberhasilan pembangunan miniatur hutan dipterokarpa. Beberapa skenario tersebut adalah :
a. Kondisi lahan terbuka dengan kondisi tanah datar dan landai (lanskap buatan)
- Penanaman dengan menggunakan pohon berdiameter besarPenanaman pohon-pohon dipterokarpa dengan diameter ≥ 10cm, menggunakan alat berat (excavator), jarak tanam 10m x 10m dengan lubang tanam 1m x 1m x 1m, pemupukan dengan menggunakan pupuk kandang dicampur top soil dengan perbandingan 1:1 (Kementerian PUPR 2014).
- Penanaman dengan menggunakan paranet Untuk penanaman dengan menggunakan paranet 45% atau 55%, semua jenis anakan dipterokarpa dapat menyesuaikan karena dengan adanya paranet kondisi iklim mikro dapat diatur sesuai dengan yang disukai oleh anakan dipterokarpa, yaitu suhu lingkungan dibawah 36⁰C, kelembaban lingkungan 60-80%, dan intensitas cahaya antara 40-60%. Sumber bibit direkomendasikan dari cabutan alam dimana perakarannya masih membawa tanah yang mengandung mikoriza sehingga dapat bersimbiosis dalam membantu akar untuk menyerap sumber air dan hara dari tanah. Bibit yang siap tanam di lapangan merupakan bibit cabutan alam yang sudah terseleksi. Jarak tanam dapat menggunakan 3m x 3m, 5m x 5m, 6m x 6m, dan 6m x 3m, ditanam selang-seling dengan tanaman jenis pionir atau pohon non diptrokarpa dari ekosistem asli hutan dipterokarpa seperti mahang (Macaranga sp.), kayu ara (Ficus sp.), jambu-jambuan (Syzygium spp.), katiau (Madhuca malaccensis), parang-parang (Fordia splendidissima), ulin (Eusideroxylon zwageri), gaharu (Aquilaria malaccensis). Ukuran lubang tanam 30cm x 30cm x 30cm, pemupukan dengan menggunakan pupuk kandang sebanyak 1-2 kg/lubang tanam (Adman et al. 2012; Mawazin dan Suhaendi 2012; Hilwan et al. 2013; Kuspradini et al. 2018; Andriansyah et al. 2019; Fajri dan Garsetiasih 2019, Fajri 2019; Karmilasanti dan Fajri 2020).
- Penanaman tanpa naungan Untuk penanaman pada kondisi lahan terbuka tanpa naungan, jenis anakan dipterokarpa yang direkomendasikan adalah S. balangeran. Sumber bibit direkomendasikan dari cabutan alam dimana perakarannya masih membawa tanah yang mengandung mikoriza sehingga dapat bersimbiosis dalam membantu akar
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
12
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
13
untuk menyerap sumber air dan hara dari tanah. Bibit yang siap tanam di lapangan merupakan bibit cabutan alam yang sudah terseleksi. Penanaman menggunakan sistim jalur dengan jarak tanam 3m x 3m atau 5m x 5m. Apabila dicampur dengan jenis pionir atau pohon dari ekosistem asli hutan dipterokarpa, jarak tanam dapat menggunakan jarak tanam 6m x 6m, 6m x 3m. Jenis pionir atau tumbuhan non dipterokarpa yang direkomendasikan adalah mahang (Macaranga sp.), laban (V. pubescens), kayu ara (Ficus sp.), jambu-jambuan (Syzigium sp.), katiau (M. malaccensis), parang-parang (F. splendidissima), gaharu (A. malaccensis). Ukuran lubang tanam 40 cm x 40 cm x 40 cm, pemupukan dengan menggunakan pupuk kandang sebanyak 3-4 kg/lubang tanam (Adman et al. 2012; Mawazin dan Suhaendi, 2012; Hilwan et al. 2013; Susilo 2016; Kuspradini et al. 2018; Andriansyah et al. 2019, Fajri dan Garsetiasih 2019; Fajri 2019; Karmilasanti dan Fajri 2020).
b. Kondisi lahan semi terbuka dengan kondisi lanskap alamiUntuk penanaman pada kondisi lahan semi terbuka, jenis anakan dipterokarpa yang direkomendasikan adalah S. balangeran, S. leprosula, D. lanceolata, H. sangal dan P. smythiesii karena jenis-jenis tersebut mampu tumbuh pada lahan yang masih terbuka dengan kondisi iklim mikro yang masih kurang bagus. Sumber bibit direkomendasikan dari cabutan alam dimana perakarannya masih membawa tanah yang mengandung mikoriza sehingga dapat bersimbiosis dalam membantu akar untuk menyerap sumber air dan hara dari tanah. Bibit yang siap tanam dilapangan merupakan bibit cabutan alam yang sudah terseleksi. Penanaman menggunakan sistim jalur dengan jarak tanam 3m x 3m atau 5m x 5m. Apabila penanaman dicampur dengan jenis non dipterokarpa dari jenis pionir atau tumbuhan dari ekosistem asli hutan dipterokarpa dapat menggunakan jarak tanam 6m x 6m atau 6 m x 3m, ditanam selang-seling. Ukuran lubang tanam 40cm x 40cm x 40cm, pemupukan dengan menggunakan pupuk kandang sebanyak 3-4 kg/lubang tanam (Omon 2006; Mawazin dan Suhaendi 2012; Hilwan et al. 2013; Widiyatno et al. 2014; Naiem et al. 2014; Susilo 2016; Fajri 2019).
c. Kondisi lahan sudah ternaungi dengan lanskap alamiUntuk penanaman pada hutan tanaman >2 tahun (sekunder muda) dan kawasan lindung PT. IHM (hutan sekunder tua), jenis-jenis dipterokarpa yang direkomendasikan adalah S. leprosula, S. pauciflora, S. parvifolia, S. smithiana, S. maxwelliana, S. macrophylla, S. atrinervosa, S. ovalis, S. johorensis, D. tempehes, D. stellatus, P. smythiesii, C. burckii, V. rassak, H. mengarawan. Sumber bibit direkomendasikan dari cabutan alam dimana perakarannya masih membawa tanah yang mengandung mikoriza sehingga dapat bersimbiosis dalam membantu akar untuk menyerap sumber air dan hara dari tanah. Bibit yang siap tanam dilapangan merupakan bibit cabutan alam yang sudah terseleksi. Penanaman menggunakan sistim jalur dengan jarak tanam 10m x 2,5m, 10m x 5m, 6m x 3m, 5m x 5m, dan 2,5m x 2,5m. Ukuran lubang tanam 30cm x 30cm x 30cm; 40cm x 40cm x 30cm. Pemupukan dapat menggunakan pupuk kandang sebanyak 2-4 kg/lubang tanam, kompos 1 kg/lubang tanam atau pupuk tablet NPK sebanyak 4 tablet/lubang tanam (Abdurachman et al. 2012; Awazin dan Suhaendi2012; Hilwan et al. 2013; Widiyatno et al. 2014; Naiem et al. 2014).
Adapun beberapa contoh jenis-jenis anakan dipterokarpa yang dapat dikembangkan dalam pembangunan miniatur hutan hutan dipterokarpa pada kawasan Ibu Kota Negara bisa dilihat pada gambar 2 dan 3.
Gambar 2. Anakan Shorea balangeran, S. leprosula dan S. laevis
Gambar 3. Anakan Shorea beccariana, S. pinanga dan S. macroptera
Penutup
Pembangunan miniatur hutan dipterokarpa dalam kawasan IKN Nusantara bertujuan untuk mendukung Masterplan Pembangunan IKN (Bappenas, 2020) dan KLHS KLHK (2019) dalam perbaikan dan pemulihan tutupan lahan di lanskap IKN dengan melakukan revitalisasi ruang terbuka hijau. Pembangunan miniatur hutan dipterokarpa dari jenis-jenis hutan dataran rendah asli Kalimantan memiliki manfaat yang sangat penting baik dibidang politik (dalam dan luar negeri), dibidang ekologi, dibidang ekonomi, dan bidang sosial. Dalam pembangunan
minatur hutan dipterokarpa diperlukan juga strategi dalam pencarian sumberdaya bibit dipterokarpa dan kegiatan pemeliharaan bibit dipersemaian yang berkualitas sehingga bisa menghasilkan bibit sesuai dengan SNI 8420:2018. Pembangunan miniatur hutan dipterokarpa juga harus didesain sesuai dengan kondisi tapaknya sehingga bisa ditentukan teknis kegiatan penanaman di lapangan dan jenis anakan dipterokarpa yang cocok untuk dikembangkan dalam pembangunan miniatur hutan dipterokarpa ini.
14
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
15
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
Daftar Pustaka
Adman, B. 2011. Pertumbuhan tiga kelas mutu bibit meranti merah pada tiga IUPHHK di Kalimantan. Jurnal Penelitian Dipterokarpa 5(2): 47-60.
Adman, B. 2012. Pemulihan, potensi jenis pohon lokal cepat tumbuh untuk batubara, lingkungan lahan pascatambang. Universitas Diponegoro.
Al Rasyid, H. et al. 1991. Vademikum Dipterocarpaceae. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Departemen Kehutanan.
Andriansyah, M. et al. 2019. Restorasi lahan pascatambang batubara di Kabupaten Berau. Laporan Hasil Penelitian. B2P2EHD.
Fajri, M. 2019. Teknik rehabilitasi lahan pascatambang galian golongan C di KHDTK Labanan Kabupaten Berau. IPB Press.
Fajri, M., Saridan, A. 2012. Kajian ekologi Parashorea malaanonan Merr di hutan penelitian Labanan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Jurnal Penelitian Dipterokarpa 6(2): 141-154.
Fajri, M. 2008. Pengenalan umum Dipterocarpaceae, kelompok jenis bernilai ekonomi tinggi. Info Teknis Dipterokarpa 2(1): 9-21.
Karmilasanti, Fajri, M. 2020. Struktur dan komposisi jenis vegetasi di hutan sekunder: Studi kasus KHDTK Labanan Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman 17(2): 69-85.
Kartawinata, K. 2013. Diversitas ekosistem alami Indonesia: Ungkapan singkat dengan sajian foto dan gambar. LIPI Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Majuakim, L., Kitayama, K. 2013. Influence of polyphenols on soil nitrogen mineralization through the format of bound protein in tropical montane forest of Mount Kinabalu, Borneo. Journal of Soil Biology and Biochemistry 57: 14-21.
Newman, M F. et al. 1999. Pedoman Identifikasi Pohon-Pohon Dipterocarpaceae Pulau Kalimantan. Prosea.
Ngatiman, Saridan, A. 2012. Ekplorasi jenis-jenis dipterokarpa di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Jurnal Penelitian Dipterokarpa 6(1): 1-10.
Omon, R M. 2006. Pertumbuhan kayu kamper dan Hopel pada lahan alang-alang dengan teknik penyiapan lahan tanam. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman 3(1): 11-23.
Pratiwi, et al. 2014. Atlas jenis-jenis pohon andalan setempat untuk rehabilitasi hutan dan lahan di Indonesia. Forda Press.
PT. ITCI Hutani Manunggal. 2019. Laporan hasil inventarisasi kawasan lindung PT. IHM. Tidak diterbitkan.
Rayan, S et al. 2010. Budidaya tumbuhan obat Jenis pasak bumi (Eurycoma sp.) pada ekosistem Hutan Dipterocarpaceae. Laporan Hasil Penelitian Program Intensif Riset KNRT. Samarinda.
Sari, N., danKarmilasanti. (2015). Kajian tempat tumbuh jenis Shorea smithiana, S. johorensis dan S. leprosula di PT. ITCI Hutani Manunggal, Kalimantan Timur. Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa 1(1): 15-28.
Saridan, A., Fajri, M. 2014. Potensi jenis dipterokarpa di hutan penelitian Labanan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Jurnal Penelitian Dipterokarpa 8(1): 7-14.
Saridan, A. 2012. Keragaman jenis dipterokarpa dan potensi pohon penghasil minyak keruing di hutan dataran rendah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Jurnal Penelitian Dipterokarpa 6(2): 75-83.
Sidiyasa, K. et al. 2013. Keragaman morfologi, ekologi, pohon induk, dan konservasi ulin. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam 10(3): 241-254.
Susanty, F H. 2015. Status riset 25 tahun plot STREK. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Hutan Dipterokarpa.
Susilo, A. 2016. Uji coba penanaman lima jenis dipterokarpa pada lahan bekas tambang di PT. Kitadin, Kalimantan Timur. Proceeding Biology Education Conference 13(1): 672-676.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara Republik Indonesia.
Wahyudi, A., Fajri, M. 2016. Karakteristik kondisi habitat dan keragaman jenis dipterocarpaceae pada hutan tropika dataran rendah. Prosiding Ekspose Hasil- Hasil Penelitian B2P2EHD.
STANDAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH BERBASIS EKOSISTEM HUTAN TROPIS MENDUKUNG
PEMBANGUNAN IKN
Ahmad Gadang PamungkasPranata Humas Ahli MadyaPusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Email: [email protected]
PPemerintah telah menetapkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang (UU)
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dari Jakarta ke lokasi baru yaitu di wilayah Kabupaten Paser Penajam dan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Seperti diketahui bahwa lokasi baru tersebut memilki karakteristik yang sangat berbeda dibanding dengan lokasi lain, khususnya yang ada di Pulau Jawa.
Salah satu perbedaan yang cukup signifikan adalah sebagian besar merupakan areal kawasan hutan, baik berupa hutan alam atau hutan tanaman. Kondisi ini menuntut strategi pembangunan yang tepat, tanpa harus mengorbankan ekosistem yang ada di antaranya sebagai habitat satwa eksotik dilindungi selain fungsi jasa lingkungan lainnya baik penyerapan karbon, perlindungan tata air, menjaga suhu udara dan lain sebagainya.
Selain itu saat ini Indonesia terikat dengan komitmen global yaitu Paris Agreement yang tercantum dalam dokumen National Determination Contribution dimana Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29% dengan skema Business as Usual dan atau 41% dengan dukungan dari pihak luar pada 2030. Selain itu dalam skema Folu net sink kita juga berkomitmen untuk mencapai net serapan karbon mulai tahun 2030.
Pemindahan lokasi Ibu Kota Negara sebagaimana sudah ditetapkan membutuhkan prasyarat agar dalam tahap perencanaan, pembangunan dan penggunaannya tetap adaptif terhadap kondisi
sumberdaya alam yang ada, khususnya terkait keberadaan satwa liar dan fungsi hutan sebagai penyedia jasa lingkungan lainnya.
Pada perencanaan, pembangunan maupun penggunaan nantinya diperlukan standar sebagai pedoman kebijakan teknis termasuk dalam pembentukan struktur ruang yang akan dibangun sehingga fungsi hutan dapat terjaga. Konsep IKN sebagai Forest City dimana 50% dari wilayahnya dipertahankan sebagai areal berhutan merupakan kebijakan yang sejalan dan harus didukung.
Ibu Kota Negara dengan Konsep Forest City
Di dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) IKN disebutkan bahwa IKN harus menerapkan 10 prinsip SMART dan Forest City yang meliputi pengelolaan berbasis daerah aliran sungai, memiliki jaringan ruang hijau, memanfaatkan 50% wilayah untuk dikembangkan, konsumsi air effisien low ecological footprint, kualitas udara baik dan suhu udara sejuk, kualitas air permukaan baik, melindungi habitat satwa, terdapat tutupan hutan yang baik dan terevitalisasinya lanskap hutan tropis dan penerapan elemen smart city dalam pengelolaan lingkungan.
Forest city atau kota berbasis lanskap adalah kota yang menempatkan ekosistem hutan sebagai pembentuk struktur ruang perkotaan, orientasi kehidupan masyarakat perkotaan, dan memfasilitasi interaksi antar kegiatan perkotaan. Forest city dilakukan melalui pendekatan multi-scale yang dimulai dengan memastikan
Satwa liar paling rentan terhadap pelaksanaan pembangunan IKN. Keberadaannya juga merupakan lokomotif bagi keberlangsungannya baik sebagai informasi keberagaman jenis hutan tropis dan kecukupan minimal kawasan hutan. Untuk itu, standar karakteristik habitat satwa liar terutama bagi spesies payung (orangutan, beruang madu) penting untuk diperhatikan.
17
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
STANDARDISASI LHK
ecoregion pendukung sistem kota bekerja secara berkelanjutan sampai perancangan infrastruktur, bangunan, ruang terbuka hijau dan biru yang terintegrasi di level tapak. Secara prinsip pembangunan forest city harus dapat memaksimalkan fungsi ekologis hutan.
Diantara kriteria forest city dalam prinsip konservasi sumberdaya alam dan kelestarian hutan adalah terjaganya habitat flora dan fauna, kawasan ekosistem esensial dan kawasan hutan dan habitat satwa dan tumbuhan liar terjaga dan terpulihkan.
Disamping itu ditekankan pula bahwa IKN harus memenuhi 4 kebutuhan feasibility lanjutan meliputi 1) Sistem sosial budaya dan pola tren pertumbuhan penduduk, 2) Sistem tata air tapak, ekosistem teluk-pesisir-laut, ekosistem karst dan hutan alam, 3) Sumberdaya hayati, habitat satwa dan konservasi eksitu, dan 4) Kelayakan KIPP, desain kota dan tapak serta pemulihan lingkungan. Khusus terkait pemullihan dan perbaikan lingkungan menyangkut kawasan pascatambang, peningkatan kualitas air permukaan, pemulihan ekosistem hutan tropis, perbaikan habitat satwa dan pengembangan masyarakat di wilayah IKN dan satelit.
Dalam Masterplan IKN, wilayah IKN terbagi menjadi 3 kawasan antara lain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Kawasan Ibukota Negara (KIKN), dan Kawasan Perluasan Ibukota Negara (KPIKN). Di dalam wilayah IKN, kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi terdapat di wilayah inti IKN (KIPP), di wilayah perluasaan IKN (KPIKN), dan wilayah sekitar IKN meliputi Teluk Balikpapan, Pegunungan Meratus dan sebelah utara wilayah IKN. Termasuk dalam wilayah teluk Balikpapan adalah Hutan Lindung Sungai Wain yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Dijumpai pula satwa beruang madu, lutung merah, rangkong, bekantan dll. Selain itu HL Sungai Wain merupakan lokasi pelepasliaran orangutan oleh Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF)Samboja. Sedangkan tumbuhan diantaranya kantong semar, Raflesia arnoldi, dan berbagai spesies lokal dan langka lainnya.
Keanekaragaman hayati di wilayah IKN berpotensi tertekan oleh keberadaan koridor lingkungan binaan. Pembangunan IKN harus memberikan perlindungan dan pengelolaan habitat dan ekosistem asli karena habitat flora fauna berperan penting mendukung keberlanjutan jasa ekosistem sebagai pengatur siklus nutrient. Dalam hal ini standar fragmentasi lahan yang ada saat ini tentu menjadi hal yang
perlu diperhatikan sehingga kelestarian satwa liar khususnya dapat dipertahankan. HL Sungai Wain juga merupakan salah satu penyedia kebutuhan air bersih bagi kawasan sekitarnya disamping fungsi jasa lingkungan lainnya.
Dalam rangka menjaga fungsi dan keberadaan ekosistem hutan yang ada maka diperlukan langkah-langkah pengamanan lingkungan diantaranya adalah penguatan ekosistem penopang melalui pengamanan kawasan ekosistem esensial dan pembangunan konektifitas infrastruktur hijau dan biru.
Strategi Perencanaan Pembangunan IKN Berbasis Ekosistem Hutan TropisPembangunan IKN harus benar-benar memperhatikan kelestarian fungsi hutan melalui beberapa strategi perencanaan pembangunan berikut diantaranya:
1. Kesesuaian standar keragaman jenis tumbuhan hutan tropis sebagai referensi restorasi areal yang perlu direhabilitasi.Rehabilitasi dan restorasi hutan yang dilakukan dapat mengacu pada standar keragaman jenis hutan sebagaimana ditunjukkan oleh kondisi Hutan Lindung Sungai Wain, Kalimantan Timur yang memiliki keragaman jenis pohon yang tinggi meliputi 385 jenis dalam luasan 3,60 ha dengan kerapatan 1.917 batang/ha, dan basal areal 20,57 m2/ha. Keragaman jenis tersebut merupakan habitat bagi berbagai jenis fauna yang ada meliputi 94 jenis hewan mamalia, 234 spesies burung, 17 jenis amphibi, 17 jenis ikan, serta 126 jenis serangga.Keragaman jenis yang ada menunjukkan kondisinya sebagai kesatuan ekosistem yang masing-masing spesies memainkan peran alamibya secara spesifik. Keragaman tersebut juga mencerminkan juga kompatibilitasnya sebagai habitat bagi satwa liar yang ada.
2. Kesesuaian standar karakteristik habitat satwa liar terutama spesies payung untuk menjaga populasi satwa liar. Kehidupan satwa liar membutuhkan kondisi minimum habitat yang memenuhi persyaratan untuk menopang berbagai aktifitas yang dia lakukan, baik sebagai penyedia makanan, bersosialisasi dengan individu lain baik dalam hal hewan tersebut merupakan hewan berkoloni maupun hidup sendiri, termasuk untuk keperluan berkembangbiak.
18
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
Dalam masing-masing aktifitas kehidupan yang dilakukan, satwa liar memerlukan habitat dengan karakteristik khas, baik dari ragam dan komposisi jenis tumbuhan, maupun sebaran umur sehingga dapat secara ideal menjadi tempat tinggal satwa liar. Termasuk dalam hal ini adalah suhu lingkungan, kondisi tapak termasuk jenis tanah, kelembaban dll.
Dalam kasus lanskap IKN, kita mengetahui keberadaan spesies payung dalam hal ini adalah satwa orang utan, dimana di dalam areal yang termasuk dalam kawasan perluasan IKN merupakan areal pelepasliaran orang utan hasil rehabilitasi yang dilakukan oleh BOSF. Menjadikan orang utan sebagai referensi utama dalam rangka menjaga habitat satwa liar yang ada di Kawasan Hutan merupakan langkah sangat bijak dan paling aman.
Sayektiningsih dan Ma'ruf (2017) menyatakan bahwa komponen vegetasi habitat orang utan Pongo pygmaeus morio meliputi keanekaragaman jenis, komposisi, dan struktur vegetasi di hutan tepi Sungai Menamang menunjukkan bahwa tingkat keanekagaman jenis pohon dan pancang adalah lebih tinggi dibandingkan semai. Hal ini sebagaimana ditunjukkan pada table 1 berikut;
Pada tingkat pohon, Lagerstroemia speciosa memiliki nilai indek nilai penting (INP) tertinggi, yaitu 24,71 %. Fordia splendidissima merupakan jenis dengan INP tertinggi pada tingkat pancang dengan INP 29,94 %. Selanjutnya, pada tingkat semai, Pterospermum diversifolium tumbuh dominan dengan INP 26,87 %. Vegetasi penyusun pada tingkat pohon terdiri dari 105 jenis, 68 genus, dan 38 suku. Euphorbiaceae merupakan suku yang paling umum dijumpai diikuti Verbenaceae, Moraceae, Lythraceae, dan Dilleniaceae. Sebanyak 137 pohon terindentifikasi sebagai anggota suku Euphorbiaceae, sebagaimana pada Tabel 2.
Secara umum, hutan tepi Sungai Menamang didominasi oleh pohon-pohon yang relatif muda yang dicirikan dengan melimpahnya pohon-pohon berdiameter ≥ 10–20 cm dan tinggi kurang dari 15 m.
Orang utan memanfaatkan tumbuh-tumbuhan hutan sebagai sumber pakan. Beberapa jenis pohon di lokasi penelitia di Hutan tepi Sungai Menamang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang berpotensi sebagai pakan orangutan disajikan dalam Tabel 3. Beberapa jenis diantaranya bahkan memiliki nilai INP tinggi baik pada tingkat pohon, pancang, dan semai.
19
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
3.
Selain sebagai sumber pakan, tumbuh-tumbuhan hutan juga dimanfaatkan sebagai tempat bersarang, diantaranya ditemukan pada pohon Lagerstroemia speciosa, Vitex pinnata, Dracontomelon dao, Dillenia excelsa, Cananga odorata, dan Macaranga gigantea.
Informasi mengenai dinamika populasi satwa liar, utamanya spesies payung yang berada di wilayah IKN juga perlu diketahui untuk menaksir daya dukung kawasan yang tersedia. Satwa liar membutuhkan luas minimal habitat dengan kualitas yang baik sebagai areal mencari makan, berkembang biak dan aktifitas lainnya.
3. Standar minimal luas areal berhutan untuk menjaga fungsinya sebagai pendukung keberadaan IKN.Hutan akan dapat berfungsi dengan baik sebagai habitat satwa liar, penyerap karbon serta jasa lingkungan lainnya apabila memiliki kondisi yang baik serta memiliki luas yang cukup. Luas hutan cukup sebagai habitat satwa liar apabila hutan yang tersedia terbukti dapat mendukung kehidupan dan keberadaan satwa liar secara lestari.
Demikian pula luas hutan yang cukup bagi jasa lingkungan lain misalnya air, maka dapat dilihat dari ketersediaan air yang dihasilkan dari kawasan hutan yang ada dengan jumlah dan kualitas yang baik.
Standar karakteristik habitat satwa liar terutama bagi spesies payung (orangutan, beruang madu) paling penting untuk diperhatikan. Hal ini mengingat keberadaan satwa liar paling rentan terhadap pembangunan IKN. Keberadaannya juga merupakan lokomotif keberlangsungan baik sebagai informasi keragaman jenis hutan tropis dan kecukupan luas kawasan hutan.
Untuk itu, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Dalam jangka pendek diperlukan segera pemahaman yang baik terhadap karakteristik habitat yang mendukung keberadaan satwa liar dimana hal ini akan mengantarkan kita kepada pemahaman pada referensi keragaman jenis tumbuhan pada hutan tropis, kecukupan luas areal jelajah satwa sebagai dasar penentuan alokasi luas dan letak dari areal hutan yang mendukung konsep IKN
20
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
sebagai forest city berbasis hutan tropis.2. Pada jangka menengah mempertimbangkan
dinamika pertambahan populasi satwa, maka perlu adanya standar pada aspek daya dukung habitat satwa sehingga dapat berjalan selaras dengan aktifitas lainnya, terutama menyangkut keberadaan satwa tertentu. Khusus untuk keberadaan orangutan perlu mendapatkan perhatian tersendiri mengingat resiko yang tinggi bila keberadaannya berdekatan dengan aktifitas manusia.
3. Pada tahap lanjut diperlukan standar batas ambang yang diperbolehkan dari aktifitas manusia (polusi suara, keramaian, polusi udara, dll.), sehingga tidak mengganggu satwa yang ada dan dapat berdampingan dengan aktifitas manusia di wilayah IKN.
Catatan Akhir
Konsep IKN sebagai Forest City dimana 50% dari wilayahnya dipertahankan sebagai areal berhutan merupakan kebijakan yang sejalan dengan karakteristik lokasi baru Ibu Kota Negara dan harus didukung. Kondisi areal berhutan diharapkan akan memberikan lingkungan yang nyaman, disamping merupakan wujud komitmen Indonesia atas berbagai isu lingkungan hidup dan kehutanan di level internasional.
Wujud dukungan tersebut di antaranya berupa ketersediaan standar instrumen yang menjamin berbagai praktek mulai perencanaan, pembangunan dan penggunaan sumberdaya alam yang berjalan effisien dan efektif, dengan tetap memperhatikan aspek kelestariannya.
Standar instrumen yang disusun diantaranya dapat bersumber dari hasil riset mengenai karakteristik habitat satwa liar sebagai referensi di dalam perencanaan, pembangunan dan penggunaan sumberdaya yang ada. Karakteristik habitat satwa liar akan memberikan informasi penting baik sebagai referensi hutan tropis maupun daya dukung dan daya tampung atas keberadaan populasi satwa liar yang masih ada.
Daftar Pustaka
Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), (2021). Masterplan IKN, BAPPENAS.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), (2020). Kajian Lingkungan Hidup Strategis Masterplan IKN, KLHK.
Tri Sayektiningsih dan Amir Ma'ruf (2017). Karakteristik Vegetasi Habitat Orangutan (Pongo Pygmaeus morio) di Hutan Tepi Sungai Menamang, Kalimantan Timur. Jurnal Wasian, 4(1), 17-26
21
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN IKN RENDAH KARBON MELALUI PENERAPAN PRINSIP BANGUNAN RAMAH LINGKUNGAN & PENGADAAN BARANG DAN
JASA RAMAH LINGKUNGAN
Pemerintah baru saja menerbitkan Undang Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). IKN disebut juga sebagai Ibu
Kota Nusantara, dimana secara konseptual, Nusantara dimaknai sebagai lautan di antara pulau dan pulau. Di dalam penjelasan UU disebutkan bahwa visi IKN adalah sebagai kota dunia yang menjadi role model dan manifestasi prinsip pembangunan berkelanjutan dan instrumen kebijakan yang telah dibangun oleh Pemerintah.
Visi besar tersebut bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai:1. Kota berkelanjutan di dunia yang menciptakan
kenyamanan, keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan rendah karbon;
2. Penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, yang memberi peluang ekonomi untuk semua melalui pengembangan potensi, inovasi dan teknologi, serta
3. Simbol identitas nasional, mempresentasikan keharmonisan dalam keragaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika.(Sumber: Penjelasan UU No. 3 Tahun 2022)
Didalam prinsip pembangunan IKN disebutkan bahwa pembangunan IKN akan menggunakan 100% konstruksi ramah lingkungan untuk setiap bangunan, komersial dan hunian, menerapkan praktek efisiensi sumberdaya dan rendah karbon.
Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) telah mengembangkan dan menerapkan beberapa perangkat dan standar yang siap digunakan untuk mendukung pencapaian prinsip pembangunan IKN tersebut. Sistem Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan, telah dikembangkan sejak tahun 2010. Bangunan Ramah Lingkungan adalah suatu bangunan yang menerapkan prinsip lingkungan dalam perancangan, pembangunan, pengoperasian dan pengelolaannya dan aspek penting dalam penanganan perubahan iklim (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8/2010). Melalui peraturan tersebut, KLHK menetapkan kriteria yang harus ada di dalam Bangunan Ramah Lingkungan, antara lain penggunaan material ramah lingkungan, terdapat sarana dan prasarana untuk konservasi sumberdaya air dalam bangunan gedung, dan lain-lain. Kriteria ini sebagai dasar bagi pengembangan perangkat pelaksanaan Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau di Indonesia. Saat ini, sertifikasi bangunan ramah lingkungan dilaksanakan oleh Green Building Council Indonesia (GBCI) sebagai Lembaga Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan yang telah diregistrasi oleh KLHK. Dengan kata lain, GBCI dalam pemantauan KLHK mengembangkan perangkat sertifikasi yang lebih teknis dan siap dimanfaatkan oleh publik. Sertifikasi bangunan ramah lingkungan juga dapat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 21 Tahun 2021
BSILHK telah mengembangkan dan menerapkan beberapa perangkat dan standar yang siap digunakan untuk mendukung pencapaian prinsip pembangunan IKN, yaitu penggunaan konstruksi ramah lingkungan dan praktek efisiensi sumberdaya dan rendah karbon.
Shelly Novi Handarini1, Amelia Agusni1, dan Nurmayanti2
1Analis Kebijakan Muda pada Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK, Email: [email protected] Kepala Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Standar Instrumen, Pusat Fasilitasi Penerapan Standar
Instrumen LHK
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
22
STANDARDISASI LHK
Tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. Sertifikasi bangunan hijau berdasarkan peraturan tersebut harus memenuhi aspek-aspek ramah lingkungan yang telah ditetapkan melalui skema penilaian kinerja Bangunan Hijau oleh Kementerian PUPR.
Pelaksanaan bangunan gedung ramah lingkungan tentu saja membutuhkan material bangunan yang juga harus ramah lingkungan. Apa itu material bangunan atau produk ramah lingkungan? Bagaimana cara mengidentifikasi suatu material itu ramah lingkungan ?
Secara prinsip, material atau produk ramah lingkungan adalah material atau produk yang dalam proses produksinya telah menerapkan aspek lingkungan, seperti efisiensi penggunaan sumberdaya baik itu energi, air, maupun bahan baku, serta memanfaatkan limbah atau used product sebagai bahan baku. Material atau produk ramah lingkungan juga dapat diartikan bahwa penggunaan produk tersebut hanya memerlukan sedikit energi atau sedikit air (hemat energi), contoh yang paling sering kita jumpai adalah produk elektronik, AC, lampu, toilet dengan sistem flushing yang hemat air.
Cara mengenali bahwa material/produk tersebut ramah lingkungan adalah melalui pemberian label/logo ramah lingkungan. Tentu saja label/logo ini tidak dicantumkan secara mandiri oleh produsen, tetapi melalui skema sertifikasi yaitu melalui serangkain proses penilaian terhadap pemenuhan standar/kriteria ramah lingkungan dan pengendalian terhadap pelaksanaan proses tersebut.
BSILHK menyelenggarakan skema label ramah lingkungan dengan program yang disebut dengan Ekolabel. Terdapat 2 (dua) tipe Ekolabel yang saat ini dilaksanakan, yaitu Ekolabel Tipe I dan Ekolabel Tipe II. Kedua tipe Ekolabel tersebut mengacu pada SNI ISO 14024 dan SNI ISO 14021 agar produk yang sudah mendapatkan logo Ekolabel dapat juga disetarakan dan diterima di negara lain yang juga memiliki program label ramah lingkungan yang sama-sama menggunakan ISO 14024 dan ISO 14021 sebagai rujukan. Pemenuhan kriteria Ekolabel dibuktikan dengan adanya logo Ekolabel Indonesia pada suatu produk atau kemasan produk yang memberikan informasi mengenai standar atau klaim lingkungan pada produk tersebut.
Dengan melihat logo Ekolabel, publik dimudahkan untuk mengenali mana produk yang memenuhi aspek ramah lingkungan. Logo Ekolabel juga sebagai intervensi KLHK kepada publik atau konsumen sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan. Logo Ekolabel diberikan oleh KHLK melalui BSILHK sebagai sistem kendali pelaksanaan skema ini. Sistem kendali ini diperkuat dengan adanya Hak Cipta terhadap logo Ekolabel Indonesia. Apabila ada pelanggaran terhadap pencantuman logo tersebut, maka KLHK dapat mengenakan sanksi sesuai dengan Undang Undang Hak Cipta. Intervensi informasi produk melalui logo Ekolabel dapat dilakukan secara masif untuk kelompok pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan/Green Public Procurement (GPP), yang kemudian menjadi
8 Prinsip Ibu Kota Negara yang diambil dari laman ikn.go.id adalah sebagai berikut:
1. Mendisain sesuai dengan kondisi alam2. Bhinneka Tunggal Ika3. Terhubung, aktif dan mudah diakses4. Rendah emisi karbon5. Sirkular dan tangguh6. Aman dan terjangkau7. Kenyamanan dan efisiensi melalui
teknologi8. Peluang ekonomi untuk semua.
Gambar 1. Konsep green building pada IKNSumber: https://ikn.go.id/storage/superhub/ministry-v2-1.jpg
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
23
semangat mewujudkan pembangunan rendah karbon yang diusung dalam pembangunan IKN.
European Commission (2008) mendefinisikan Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan atau Green Public Procurement (GPP) sebagai proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah melalui pengurangan dampak terhadap lingkungan dengan memperhatikan siklus hidup (life-cycle) produk jika dibandingkan dengan pengadaan barang dan jasa yang memiliki kesamaan fungsi lainnya. Memasukkan kriteria ramah lingkungan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terkait pengurangan karbon, peningkatan kualitas udara dan air, dan pengurangan limbah memungkinkan mengubah tujuan kebijakan lingkungan menjadi tindakan nyata. Pengadaan barang dan jasa oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sejalan dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia. Kebijakan pengadaan barang dan Jasa merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendorong ekonomi Indonesia tumbuh ke arah ekonomi hijau (green economy). Pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan merupakan bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan khususnya dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa di Indonesia ke arah yang lebih efisien.
Pengembangan kebijakan label ramah
lingkungan dan pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan telah diamanatkan dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya Pasal 43 ayat (3) huruf a mengenai pengadaan barang/jasa ramah lingkungan, dan huruf g mengenai sistem label ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan agenda internasional dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. Pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan dapat berperan mengatasi masalah lingkungan antara lain deforestasi, emisi gas rumah kaca, penggunaan air, efisiensi energi dan penggunaan sumber daya, polusi udara, air dan tanah, limbah dan pertanian berkelanjutan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk pengadaan Barang dan Jasa Lingkungan Hidup, dan telah ditetapkan sebagai Peraturan Menteri LHK Nomor 5 Tahun 2019. Kriteria Label Ramah Lingkungan Hidup yang diterapkan terhadap barang dan jasa antara lain: (1) Berbasis penggunaan energi; (2) Berbahan baku atau berbasis sumber daya alam, dan (3) Berbahan daur ulang.
Pada lampiran Peraturan Menteri LHK Nomor 5 Tahun 2019 terdapat 6 (enam) barang dan
Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup
Tabel 1. Daftar Rujukan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
24
jasa ramah lingkungan yaitu kertas fotokopi bersertifikat Ekolabel, folder file bersertifikat Ekolabel, kayu untuk furnitur bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), Dua produk teknologi pengolah limbah medis untuk fasilitas pelayanan kesehatan terverifikasi Teknologi Ramah Lingkungan (TRL), dan Piranti Pengkondisi Udara (Air Conditioning/AC) berlabel tanda Hemat Energi.
Penambahan daftar barang dan jasa ramah lingkungan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2019 dapat dilakukan sebanyak satu kali dalam satu tahun dan sedikitnya satu kali dalam kurun waktu lima tahun dilakukan evaluasi terhadap produk barang dan jasa ramah lingkungan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Keputusan Menteri LHK No. SK. 1207/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2021 Tentang Penambahan Daftar Rujukan Barang dan Jasa Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan, pada Tahun 2021, terdapat penambahan produk ramah lingkungan sebanyak 3 (tiga) produk, yaitu kayu olahan untuk konstruksi bersertifikat SVLK, Beton bersertifikat Ekolabel, dan Semen yang memenuhi Standar Industri Hijau (SIH). Jumlah produk ramah lingkungan tersebut dimungkinkan akan bertambah pada waktu mendatang.
Penambahan daftar rujukan produk ramah lingkungan untuk pengadaan barang dan
jasa pemerintah terdiri dari 3 (tiga) produk ramah lingkungan dengan kategori kayu untuk konstruksi dan material konstruksi meliputi Beton dan Semen. Pembangunan gedung pemerintah, gedung untuk fasilitas umum termasuk fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta infrastruktur transportasi publik pada waktu mendatang di IKN tidak lepas dari penggunaan bahan material kayu, beton dan semen sebagai bahan utama penyelenggaraan konstruksi bangunan.
Pembangunan infrastruktur pemerintah dan fasilitas umum dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh Kementerian PUPR. Regulasi kebijakan di lingkup Kementerian PUPR terkait konstruksi berkelanjutan sudah sejalan dengan semangat Ramah Lingkungan yang banyak didengungkan saat ini untuk dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pengadaan barang dan jasa pemerintah hendaknya sudah mempertimbangkan kriteria ramah lingkungan untuk peningkatan kualitas lingkungan.
Perubahan pola pikir dan perilaku dalam penerapan pengadaan barang dan jasa pemerintah dari bentuk konvensional menjadi ramah lingkungan sampai saat ini masih berproses. Banyak hal yang harus dibangun. Tidak mudah merubah kebiasaan dan sistem yang sudah ada ditengah derasnya arus informasi produk dan keberagaman produk dari
Tabel 2. Penambahan Daftar Rujukan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan
Sumber : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 1207/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 12/2021 Tahun 2021 tentang Penambahan Daftar Rujukan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
25
produsen sebagai bagian dari marketing. Perlu intervensi yang sistematif untuk menggerakkan produsen dalam menghasilkan produk dan jasa ramah lingkungan sekaligus menggerakkan public sebagai kelompok konsumen.
Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan/GPP dapat menjadi purchasing power, menjadi kekuatan yang menggerakkan perubahan pola pikir dan perilaku tersebut. Menjadi power karena belanja barang dan jasa pemerintah lebih dari 30% APBN. Apabila kebijakan GPP dapat dilaksanakan oleh seluruh pemerintah Pusat dan Daerah, maka jelas hal ini menjadi pendorong dan penggerak yang nyata dan signifikan.
Daftar Pustaka
Bappenas RI. (2022). Delapan Prinsip Ibu Kota Negara. Diambil 21 Maret 2022 dari IKN website: https://ikn.go.id.
Commission of The European Communities. (2008). Procurement for a Better Environment, 2008. Brussel.
European Union. (2011). Buying Green! A Handbook on Green Procurement, 2nd Edition. Brussels: European Union.
Menteri Lingkungan Hidup RI. (2019). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2019 tentang tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup. Kriteria Label Ramah Lingkungan Hidup yang diterapkan terhadap barang dan jasa antara lain.
Menteri Lingkungan Hidup RI. (2021). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 1207/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2021 Tahun 2021 tentang Penambahan Daftar Rujukan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup.
Menteri Lingkungan Hidup RI. (2010) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan.
Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan. (2021). Panduan Produk Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan. Jakarta : Pustanlinghut.
Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan. (2021). Laporan Kinerja Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan. Jakarta: Pustanlinghut.
Republik Indonesia. (2022). Undang-undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
26
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
27
IDE & OPINI
INTEGRASI PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA BARU DAN DAERAH PENYANGGANYA
Ibu kota negara merupakan cermin yang memantulkan keberagaman suatu negara. Walaupun belum ada UU yang mengatur
tentang ibu kota negara secara khusus, Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 jo. UU PNPS No.2 Tahun 1961. Regulasi yang terbit berikutnya merupakan aturan yang menetapkan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), mulai dari UU No. 11 Tahun 1990, UU No. 34 Tahun 1999, hingga terakhir, yang masih berlaku hingga saat ini, diatur melalui UU No. No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi khususnya lingkungan Jakarta dianggap telah over capacity. Jakarta menghadapi berbagai isu dan permasalahan dalam pembangunan perkotaan. Atmawidjaja dkk (2015) menyebutkan isu dan permasalahan pembangunan perkotaan diantaranya yaitu:
1. Urbanisasi dan peningkatan penduduk perkotaan secara signifikan
2. Semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan
3. Kemiskinan di perkotaan4. Kapasitas daerah dalam pengembangan dan
pengelolaan perkotaan di era desentralisasi5. Tingkat pertumbuhan antar kota yang belum
berkembangData BPS (2021) menunjukkan bahwa Jakarta pada tahun 2020 memiliki populasi sebanyak 10.562.088, dengan kepadatan penduduk 14.555 orang setiap kilometer perseginya. Kondisi tersebut telah melampaui daya dukung yang mampu ditopang oleh Jakarta. Selain itu pembangunan yang mengabaikan
keberadaan lingkungan telah ikut berperan dalam menurunkan daya dukung lingkungan. Hal itu telah mendorong pemerintah untuk kembali mempertimbangkan perpindahan ibu kota negara.
Perpindahan ibu kota negara dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan bukan lagi sekedar wacana. Terbitnya UU nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang ditandatangani dan resmi diundangkan pada 15 Februari 2022 lalu menjadi bukti keseriusan pemerintah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pembentukan ibu kota negara yang bernama Nusantara sebagai ibu kota negara serta pembentukan otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
Ibu kota negara baru yang nantinya akan menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional memiliki visi dalam pembangunannya. Visi tersebut adalah sebagai kota paling berkelanjutan di dunia, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia. Visi tersebut dijabarkan dalam 8 prinsip ibu kota negara yaitu mendesain sesuai kondisi alam, Bhinneka Tunggal Ika, terhubung aktif dan mudah diakses, sirkuler dan tangguh, nyaman dan efisien melalui teknologi, aman dan terjangkau, rendah emisi karbon dan peluang ekonomi untuk semua.
Namun demikian, keberhasilan untuk melakukan pembangunan Smart City di IKNB sebaiknya
Wilayah penyangga Ibu Kota Negara Baru (IKNB) berperan penting dalam mendukung tercapainya konsep Smart City. Namun pada implementasinya penyelarasan pembangunan IKNB dengan wilayah penyangganya menghadapi tantangan kondisi lokal wilayah penyangga IKNB. Konsep pembangunan terintegrasi dapat menjadi solusi dalam penyelarasan pembangunan tersebut.
Galih Kartika SariPusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. E-mail: [email protected]
diikuti dengan keberhasilan pembenahan di wilayah penyangganya. Penerapan standar dalam pembangunan infrastruktur baik dalam pembangunan IKN maupun infrastruktur pendukung di daerah penyangga akan membantu pencapaian kondisi ideal IKNB dan daerah penyangganya.
Smart City dalam Tataran Konsep
Smart City sebagai konsep dalam ibu kota negara baru merupakan konsep yang digunakan untuk menghadapi tantangan-tantangan perkembangan kota modern dimasa yang akan datang. Konsep yang populer dalam beberapa dekade terakhir tersebut diasumsikan mampu untuk mengatasi pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang kian meningkat serta dianggap sebagai konsep yang mampu memenuhi kebutuhan akan cara-cara baru dan inovatif untuk mengelola kompleksitas kehidupan perkotaan (Winkowska dkk, 2019). Sebagai pembelajaran dari pembangunan Jakarta, konsep smart city yang diterapkan pada ibu kota negara baru diharapkan mampu mengatasi isu dan permasalahan dalam pembangunan perkotaan di masa yang akan datang. Namun demikian, untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan data dan teknologi yang mampu untuk meningkatkan efisiensi, pembangunan ekonomi, keberlanjutan, dan kualitas hidup masyarakat.
Giffinger dkk (2007) menyebutkan bahwa smart city memiliki 6 domain sebagaimana digambarkan pada gambar di atas. Giffinger dkk juga menjabarkan masing masing domain tersebut sebagai berikut:
1. Smart economy: terdiri dari fitur-fitur seputar daya saing ekonomi termasuk didalamnya adalah kewirausahaan, inovasi, fleksibilitas, produktivitas pasar tenaga kera, merek dagang dan partisipasi di pasar global.
2. Smart people: tidak hanya menyangkut tingkat kualifikasi atau pendidikan yang diterima warga negara, tetapi juga interaksi sosial tambahan dan persepsinya tentang kehidupan publik.
3. Smart governance: menyangkut keterlibatan politik, pelayanan terhadap warga, dan fungsi administrasi.
4. Smart mobility: mencakup aksesibilitas lokal dan global dengan kehadiran TIK dan sistem transportasi yang berkelanjutan dan relevan.
5. Smart environment: memperhatikan kondisi alam yang menarik termasuk ruang hijau, iklim yang tidak terlalu ekstrim, pengurangan polusi, pengelolaan sumber daya, dan upaya untuk mencapai perlindungan lingkungan.
6. Smart living: mencakup banyak fitur kualitas hidup yang terdiri dari kesehatan, perumahan, budaya, pariwisata, dan keselamatan.
Smart City merupakan kota yang dirancang dengan menggunakan teknologi dan data untuk meningkatkan efisiensi, pembangunan ekonomi, keberlanjutan, dan kualitas hidup warga di wilayah perkotaan. Keberlanjutan sebagai salah satu konsep yang digunakan dalam smart city mendorong untuk digunakannya teknologi bersih. Teknologi bersih tersebut meliputi untuk energi, transportasi, dan kesehatan. Van Lendegem (2011) mendefiniskan key driver bagi pengembangan konsep Smart City pada masing-masing parameternya.
28
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
Key Driver Pengembangan Konsep Smart City menurut Van Lendegem (2011)
Parameter Key DriverSmart Governance 1. Proses demokrasi dan inklusi
2. Administrasi tata kelola pemerintahan yang saling terkoneksi serta terintegrasi3. Peningkatan akses terhadap pelayanan
Smart People 1. Peningkatan pola edukasi2. Pengontrolan pembelajaran melalui Remote e-education Solution 3. Masyarakat yang terinformasi secara lebih baik
Smart Environment 1. Lingkungan dikelola secara berkelanjutan (sustainable)2. Mengurangi penggunaan energi melalui inovasi teknologi, konservasi energi dan daur ulang material
Smart Mobility 1. Sistem transportasi yang cerdas dan efisien2. Memanfaatkan dan mengefisienkan jaringan pergerakan kendaraan,
orang dan barang untuk mengurangi kemacetan3. Penerapan “new social attitude” seperti berbagi (sharing) kendaraan,
opsi sepeda-mobil
Smart Economy 1. Kompetisi regional/global2. Akses broadband untuk seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan peluang B2B3. Lokasi yang independen, membantu mengelola populasi dalam suatu area4. Transaksi elektronis proses bisnis dalam semua bidang (e-banking, e-shopping, e-actuation, dll)
Smart Living 1. Akses yang berkualitas tinggi terhadap layanan kesehatan (e-health, remote health monitoring)2. Manajemen electronic health record3. Otomatisasi rumah, rumah cerdas dan layanan smart building4. Akses terhadap berbagai jenis layanan sosial
Pencapaian kondisi yang diinginkan dalam pembangunan kota dengan konsep Smart City membutuhkan standar sebagai acuan. Standar menurut International Standard Organization (ISO) merupakan proses perumusan dan penerapan aturan untuk pendekatan yang teratur terhadap kegiatan tertentu untuk keuntungan dan dengan kerjasama semua pihak, khususnya untuk promosi ekonomi keseluruhan yang optimal dengan mempertimbangkan kondisi fungsional dan persyaratan keselamatan (American National Standard Institute, 2002). Standar digunakan untuk membantu mengatur bagaimana smart city berfungsi dan berkontribusi untuk memberikan gambaran penerapan konsep smart city diwilayahnya.
Daerah Penyangga dan Pembangunan Terintegrasi
Tantangan lain yang dihadapi dalam pembangunan IKNB adalah menyiapkan daerah penyangga agar mampu mendukung keberadaan IKN. Pembangunan Ibu Kota Nusantara memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kota dan provinsi disekitarnya baik dampak positif maupun dampak negatif. Keberadaan ibu kota negara dengan konsep smart city membutuhkan dukungan dari daerah penyangga di sekitarnya. Hal itu seperti Jakarta dengan wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasinya. Oleh karena itu, pembangunan IKN sebaiknya dibarengi dengan penyiapan dan pembangunan daerah-daerah penyangga ibu kota nantinya. Selama ini Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara mendapatkan suplai sumber daya dari beberpa provinsi disekitarnya. Perpindahan ibu kota akan mendorong terjadinya perpindahan penduduk yang masif
29
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
baik ke ibu kota negara maupun ke kota-kota penyangga di sekitarnya.
Wilayah penyangga ibu kota negara baru meliputi Balikpapan, Samarinda, perbatasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara. Selama ini daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang kerap menghadapi kejadian banjir. Di Kota Samarinda kejadian banjir disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor alam seperti tingginya curah hujan, topografi wilayah, dan pasang surut air Sungai Mahakam, dan faktor kedua adalah manusia yaitu utamanya bersumber pada unsur pertumbuhan penduduk (Setiawan, dkk, 2020).
Sedangkan di Kota Balikpapan, khususnya di DAS Ampal dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Awaliyah dkk, 2020). Faktor internal tersebut di antaranya adalah kapasitas sungai, kapasitas drainase, infiltrasi tanah, tinggi aliran air, limpasan air, erosi, sedimentasi, luas DAS, bentuk DAS, topografi, morfometri, vegetasi. Sedangkan faktor ekternal yang mempengaruhinya adalah intensitas hujan, tata guna lahan, perilaku membuang sampah, kawasan kumuh, perencanaan sistem pengendalian banjir, pemeliharaan bendali, pemeliharaan drainase, jarak bangunan terhadap sungai, lokasi permukiman di sempadan sungai, serta aliran balik (back water).
Hasil penelitian di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda menunjukkan bahwa sistem drainase perkotaan sebagai salah satu penyebab terjadinya banjir. Rahardjo dalam tulisannya pada tahun 2014 juga mengatakan bahwa terdapat tujuh penyebab terjadinya banjir di wilayah perkotaan. Tujuh penyebab banjir tersebut di antaranya yaitu pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, tidak adanya pola hidup bersih di masyarakat umum, tidak adanya sistem perencanaan dan pemeliharaan drainase kota yang baik, tidak konsistennya pihak berwenang terhadap implementasi RTRW (Rencana tata Ruang dan Wilayah). Selain itu tidak adanya upaya konservasi faktor penyeimbang lingkungan air, terjadinya penurunan muka tanah dan curah hujan yang sangat tinggi.
Kondisi-kondisi pada wilayah penyangga IKNB tersebut tentu saja membutuhkan pemecahannya. Hal itu dalam upaya untuk mendukung IKNB yang dirancang sebagai kota dunia untuk semua yang memiliki 8 prinsip dan 24 indikator kinerja kunci. Prinsip dan indikator tersebut mendukung IKN menjadi kota yang mampu untuk mendukung dirinya sendiri.
8 Prinsip dan 24 Indikator Kinerja Kunci Pembangunan IKN sebagai Kota Dunia untuk semua.
Prinsip Indikator
1. Mendesain sesuai kondisi alam
• >75% dari 256 k Ha area untuk ruang hijau (65%area dilindungi dan 10% produksi makanan)
• 100% penduduk dapat mengakses ruang hijau rekreasi dan 10 menit
• 100% penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat institutional, komersial, dan hunian (bangunan >4 lantai)
2. Bhinneka Tunggal Ika
• 100% terintegrasi seluruh penduduk- yang ada dan yang baru
• 100% warga dapat mengakses layanan sosial/masyarakat dalam waktu 10 menit
• 100% ruang public dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal dan desain inklusif
3. Terhubung, aktif dan mudah diakses
• 80% perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif
• 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik
• <50 menit koneksi transit ekspres dari KIPP kebandara strategis pada tahun 2030
4. Rendah emisi karbon
• Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi IKN
• 60% penghematan energi untuk konservasi energi dalam gedung
• Net Zero emission untuk IKN (saat beroperasi) di 2045 di kawasan 256 Ha
5. Sirkular dan tangguh
• >10% dari lahan 256 K Ha tersedia untuk kebutuhan produksi pangan
• 60% daur ulang semua timbulan limbah di tahun 2045
• 100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035
30
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
Prinsip Indikator
6. Aman dan terjangkau
• Tp-10 EIU Liveable City di dunia pada tahun 2045
• Pemukiman yang ada dan terencana di kawasan 256 K memiliki akses terhadap infrastruktur penting di 2045
• Perumahan yang adil dengan perbandingan 1:3:6 untuk jenis mewah, menengah, dan sederhana
7. Nyaman dan efisien melalui teknologi
• Mewujudkan peringkat sangat tinggi dalam E-Government Development Index (EGDI) oleh UN
• 100% konektivitas digital dan ICT untuk semua penduduk dan bisnis
• >75% Bussiness Satisfaction dengan peringkat Digital Services
8. Peluang ekonomi untuk semua
• 0% kemiskinan pada populasi IKN pada tahun 2015
• PDB per Kapita negara berpendapatan tinggi
• Rasio Gini regional terendah di Indonesia di tahun 2045
(sumber: Armundito (2022)
Pembangunan yang terintegrasi antara wilayah IKNB dengan wilayah penyangganya dapat menjadi solusi menutup “gap” yang ada. Istilah terintegrasi tersebut bukan hanya istilah tetapi merupakan konsep yang kompleks dan harus disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kondisi lokal lainnya. Kata “Integrasi” dalam pembangunan mengutip Prayitno dalam tulisannya dapat dimulai dari integrasi pembangunan di berbagai level pemerintahan, kemudian pembangunan tersebut mesti terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan terakhir pembangunan harus terintegrasi antar fungsi dan antar sektor.
Penyiapan-penyiapan untuk memenuhi 8 prinsip pembangunan IKNB yang sedang dan
akan dilaksanakan sebaiknya mencakup penguatan-penguatan elemen penting dalam pengembangan daerah penyangganya. Elemen penting yang memerlukan penguatan tersebut menurut Pranadji (2006), diantaranya:
1. Penguatan faktor-faktor yang mendukung perbaikan sistem produksi di daerah penyangga
2. Mempercepat proses transformasi faktor-faktor yang mendukung perbaikan sistem ekonomi di daerah penyangga
3. Mentransformasikan faktor tatanan politik dan pemerintahan (desentralisasi) dalam pembangunan ekonomi di daerah penyangga
4. Mentransformasikan faktor-faktor yang mendukung sistem manajemen dan keorganisasian ekonomi di daerah penyangga.
Konsep Smart City yang diusung oleh IKNB merupakan konsep yang ambisius dan pada implementasinya didukung dengan berbagai standar yang disusun dan dipenuhi.
Pembenahan daerah penyangga calon ibu kota negara baru dapat dilakukan melalui pembangunan terintegrasi. Terintegrasi yang dimaksudkan tersebut meliputi integrasi berbagai level pemerintahan, tata ruang dan antar fungsi serta sektor.
Pembangunan terintegrasi antara IKNB dan wilayah penyangganya memerlukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama berbagai sektor di tingkat berbagai level pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan strategi koordinasi yang efektif untuk pengintegrasian pembangunan antara wilayah IKNB dengan wilayah penyangga.
Daftar Pustaka
Armundito, E. 2022. Arah Standar Bidang Lingkungan Hidup dalam Mendukung Ekonomi Sirkular dan Ibu Kota Negara. Direktorat Lingkungan Hidup, Bappenas. Power Point Presentasi.
Atmawidjaja, E.S., Sastra, Z dan Akbar, N. R., 2015. Kajian Pengembangan Smart City di Indonesia. Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan umum.
Awaliyah, N., Ariyaningsih, dan Ghozali, A. 2020. Analisis Faktor yang Berpengaruh terhadap Terjadinya Banjir di DAS Ampal/Klandasan Besar dan Kesesuaian Program dengan Faktor Penangannya.
31
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
Jurnal Penataan Ruang Vol. 15, No. 2. ISSN: 2716-4972.
Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanovi, N., & Meijers, E. (2007). Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities. Vienna, Austria: Centre of Regional Science (SRF), Vienna University of Technology. Available at http://www.smartcities. eu/download/smart_cities_final_report.pdf. diakses pada 2 Maret 2022.
Pranadji, T. 2006. Pengembangan Daerah Penyangga sebagai Upaya Pengendalian Arus Urbanisasi. Analisis Kebijakan Pertanian, Volumen 4 No. 4, Desember 2006:327-341.
Prayitno. 2020. Pembangunan (Infrastruktur) Terintegrasi. https://birokratmenulis.org/pembangunan-infrastruktur-terintegrasi/. Diakses pada tanggal 8 Maret 2022.
Rahardjo, P.N. 2014. 7 Penyebab Banjir di Wilayah Perkotaan yang Padat Penduduknya. JAI Vol. 7 No. 2, 2014.
Setiawan, H., Jalil, M., E, M.E., Purwadi, F., S, C.A., Brata, A.W., & Jufda, A.S. 2020. Analisis Penyebab Banjir di Kota Samarinda. Jurnal Geografi Gea, Volume 20, No. 1, April 2020. E-ISSN 2549-7529; p-ISSN 1412-0313. https://ejournal.upi.edu/index.php/gea
Van Len Degem. 2012. ICT Insfrastructure ad Key Enabler of Smart Cites. Catel Luccent. Bell Labs. Aalbogs.
Winkowska, J., Szpilko, D., & Pejic, S. 2019. Smart City Concept in The Light of Literature Review. Engineering Management in Production and Service Vol. 11, Issue 2. 2019, P: 70-86.
32
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
DARMA PENYULUHANAN KEHUTANAN MENYONGSONG ERA STANDARDISASI
Berdasarkan tinjauan sejarah, penyuluhan lahir setelah forum diskusi-diskusi di Kampus Oxford dan Cambridge, Inggris
pada tahun 1850. Diskusi-diskusi yang diselenggarakan terkait tentang fenomena problematika yang berkembang di masyarakat akibat cepatnya pertumbuhan penduduk di sekitar kawasan industri. Topik penyuluhan di bidang pertanian mulai muncul pada dekade 1890 sebagai upaya untuk memecahkan berbagai masalah pertanian di pedesaan (Hariadi, 2021). Program penyuluhan masuk ke Indonesia pada masa pendudukan Belanda, tepatnya pada tahun 1910 dengan berdirinya Dinas Penyuluhan Pertanian (Landbouw Voorlichting Dienst). Kata Voorlichting berarti penerangan, yakni memberikan jalan ke depan untuk membantu orang untuk menemukan jalannya. Oleh karena itu, dalam bahasa Indonesia, penyuluh itu berasal dari kata suluh, yang artinya obor. Salah satu fungsi obor adalah sebagai penerang di sekitarnya.
Menurut Hariadi dan Subejo (2021), penyuluhan dan ilmu penyuluhan lahir di sektor pertanian dan terus berkembang seiring dengan pesatnya pembangunan di berbagai sektor kehidupan. Peran penting penyuluhan semakin pesat baik di tingkat nasional, regional maupun global. Berbagai upaya masyarakat internasional untuk mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di era komunikasi ini memerlukan berbagai pendekatan dan strategi penyuluhan yang efektif, efisien. Hal ini tentu saja memberikan manfaat yang signifikan untuk percepatan kualitas kehidupan masyarakat (quality life improvement).
Pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi tidak hanya pada bangunan infrastruktur (fisik), namun pengembangan sumberdaya manusia yang berperan dalam percepatan (katalisator) dan keberhasilan pembangunan disegala bidang. Hal ini tentu meningkatkan kebutuhan profesi penyuluh. Para penyuluh dibutuhkan pada lembaga-lembag internasional yang berafiliasi dengan PBB (FAO, UNDP, UNESCO, UNHCR, WHO, WFP, WWF, dll) maupun lembaga lain seperti research center, korporasi bisnis, lembaga pemberdayaan masyarakat, NGO, lembaga penyiaran. Demikian juga di semua Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) P.14/2019 tentang Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan, selain ada penyuluh kehutanan PNS, juga ada penyuluh kehutanan swadaya masyarakat dan penyuluh kehutanan swasta.
Tulisan ini menjelaskan sekilas sejarah penyuluhan, perkembangan ilmu dan peran penyuluhan dalam pembangunan, peraturan perundang-undangan tentang penyuluhan, dan peran penyuluhan di era standardisasi. Terkait dengan era standardisasi, organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki eselon I baru, yaitu Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) yang membutuhkan peran penyuluh kehutanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya:
Peran penyuluh kehutanan sebagai salah satu ujung tombak di lapangan diharapkan dapat berkonstribusi dalam mengimplementasikan standar kepada para pelaku utama dan pelaku usaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga pengendalian lingkungan hidup dan kehutanan dalam akselerasi pertumbuhan investasi dan usaha melalui intervensi standardisasi instrumen lingkungan hidup dan kehutanan dapat terwujud.
Lukman HakimPenyuluh Kehutanan MadyaBalai Besar Pengujian Standar dan Instrumen Kehutanan Yogyakarta. E-mail: [email protected]
IDE & OPINI
33
Mengenal Seluk Beluk Penyuluh Kehutanan
Jabatan fungsional penyuluh kehutanan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permen PAN RB) 73/2020 adalah jabatan yang diduduki PNS, mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan penyuluhan kehutanan. Sedangkan penyuluhan kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama (petani dan keluarga) serta pelaku usaha (pengusaha) agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Seorang penyuluh yang profesional harus memiliki kemampuan berkomunikasi, menghayati profesinya, serta dekat dan mencintai masyarakat yang didampinginya. Perannya sebagai fasilitator (memberikan fasilitasi/kemudahan), mediator (penghubung dengan lembaga pemerintah/non pemerintah), dinamisator (mampu mendinamiskan) kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan (Slameto dan Adriyani, 2021). Sasaran penyuluhan kehutanan adalah pihak yang paling berhak menerima manfaat penyuluhan kehutanan yang meliputi sasaran utama dan sasaran antara. Sasaran utama adalah pelaku utama dan pelaku usaha dalam bidang kehutanan yang menerima manfaat langsung penyuluhan kehutanan. Sedangkan sasaran antara adalah pemangku kepentingan yang tidak secara langsung menerima manfaat penyuluhan kehutanan, antara lain kelompok atau lembaga pemerhati kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat. Pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan beserta keluarga intinya. Sedangkan pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
Jenjang jabatan fungsional penyuluh kehutanan meliputi kategori keterampilan dan keahlian. Kategori keterampilan terdiri dari penyuluh kehutanan pemula, penyuluh kehutanan terampil, penyuluh kehutanan mahir, dan penyuluh kehutanan penyelia. sedangkan kategori keahlian meliputi: ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Orang
bijak berkata bahwa perencanaan yang baik merupakan setengah dari modal untuk mencapai keberhasilan suatu misi atau kegiatan. Programa Penyuluhan Kehutanan merupakan dokumen perencanaan yang akan diacu oleh para penyuluh kehutanan setiap tahunnya. Dokumen penting ini diatur dalam Permen LHK P.14/2019 tentang Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan.
Pengertian Programa Penyuluhan Kehutanan adalah rencana tertulis kegiatan penyuluhan kehutanan dalam satu tahun yang disusun secara sistematis sebagai bahan perencanaan pembangunan kehutanan. Kemudian ditindaklunjuti oleh para penyuluh PNS secara perorangan untuk membuat Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan (RKTPK) yang berisi kegiatan Penyuluhan kehutanan yang akan dilakukan dalam satu tahun.
Programa Penyuluhan Kehutanan disusun pada setiap tingkat wilayah kerja pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan yang meliputi: Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat Unit Pelaksana Teknis Daerah/Cabang Dinas Kehutanan (UPTD/CDK), tingkat provinsi, tingkat UPT KLHK tingkat nasional. Programa ini pada setiap tingkatan harus memperhatikan keterpaduan dan kesinergian penyuluhan kehutanan pada setiap unit kerja. Dokumen perencanaan ini disusun oleh tim yang ditetapkan kepala unit kerja yang beranggotakan seluruh pejabat fungsional penyuluh kehutanan PNS lingkup unit kerja. Fasilitasi kegiatan oleh unit kerja yang meliputi identifikasi potensi wilayah, pengolahan data, penyusunan, dan pembahasan. Pengesahan Programa Penyuluhan Kehutanan oleh Kepala UPTD/CDK, untuk tingkat UPTD/CDK, Kepala Dinas Provinsi, tingkat provinsi, Kepala UPT KLHK, tingkat UPT KLHK, dan Kepala Badan P2SDM, tingkat nasional. Pengesahan dilakukan paling lambat bulan Februari tahun berjalan untuk tingkat UPTD/CDK, bulan Maret tingkat provinsi dan UPT KLHK, dan bulan April tingkat nasional. Programa Penyuluhan Kehutanan yang telah disahkan digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan kehutanan pada tahun berikutnya.
Programa penyuluhan kehutanan yang telah disahkan sebagai dasar penyusunan RKTPK yang disusun oleh penyuluh kehutanan PNS sesuai wilayah kerja yang bersangkutan. RKTPK disahkan oleh atasan langsung penyuluh
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
34
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
kehutanan PNS sebagai pedoman dalam melaksanakan penyuluhan kehutanan pada tahun berjalan. Untuk mengetahui efektifitas dan kesesuaian pelaksanaan programa penyuluhan kehutanan dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan paling sedikit tiga bulan sekali. Kegiatan ini dilakukan oleh Kepala UPT KLHK untuk tingkat UPT KLHK dan Kepala Badan P2SDM tingkat nasional. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan revisi dan/atau penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan pada tahun berikutnya. Pembiayaan programa penyuluhan kehutanan terdiri atas pembiayaan penyusunan, pembiayaan pelaksanaan kegiatan, dan pembiayaan monitoring dan evaluasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
Tugas dan unsur kegiatan penyuluh kehutanan yang dapat dinilai menjadi angka kredit meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan,
pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Sebagai contoh pembagian tugas kategori keahlian pada kegiatan persiapan penyuluh kehutanan yang tertuang dalam lampiran II Permen PAN dan RB 73/2020 dapat dilihat pada matrik 1.
Kegiatan persiapan penyuluh kehutanan berdasarkan matrik 1 di atas, meliputi kegiatan pengumpulan data programa penyuluhan kehutanan, penyusunan programa penyuluhan kehutanan dan rencana kerja tahunan penyuluh kehutanan. Kegiatan persiapan ini sangat krusial dan mempengaruhi kinerja sehingga perlu mendapatkan dukungan dari managemen. Programa penyuluhan kehutanan tingkat UPT KLHK difasilitasi oleh unit kerja masing-masing dan pengesahannya dilakukan Kepala UPT KLHK. Programa ini sebagai pedoman bagi Penyuluh Kehutanan PNS dalam melaksanakan Penyuluhan Kehutanan pada tahun berjalan.
Matrik 1. Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Kategori Keahlian
No Unsur Sub-Unsur Uraian Kegiatan/Tugas Hasil Kerja/Output Pelaksana Tugas
1. Persiapan Penyuluhan Kehutanan
A. Pengumpulan data Programa Penyuluhan Kehutanan
1. Menyusun instrumen identifikasi data potensi wilayah
Instrumen identifikasi data potensi wilayah
Ahli Muda
2. Mengidentikasi data potensi wilayah
Dokumen data potensi wilayah
Ahli Pertama
3. Mengolah data potensi wilayah
Laporan hasil pengolahan data potensi wilayah
Ahli Muda
4. Menganalisis data potensi wilayah
Laporan hasil analisis data potensi wilayah
Ahli Madya
B. Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan
Menyusun programa penyuluhan kehutanan
Dokumen programa penyuluhan kehutanan
Ahli Pertama , Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama
C. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan
Menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan
Dokumen RKTPK Ahli Pertama , Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama
35
Modalitas Badan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Modalitas BSILHK berasal dari dua lembaga yaitu eks Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi (BLI) yang menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi dan eks Pusat Standardisasi Lingkungan (Pustanling). Adapun modalitas yang tertuang dalam naskah draf Rencana Strategis Tahun 2022-2024 BSILHK, antara lain:
1. Sumber Daya Manusia yang memperkuat BSILHK berjumlah 1.317 orang yang secara rinci terdiri dari 119 struktural, 181 pengendali ekosistem, 24 pengendali dampak lingkungan, 41 penyuluh kehutanan, 13 analis kebijakan, 129 fungsional lainnya, 456 staf umum, 5 tenaga perbantuan, dan 349 PPNPN.
2. Dokumen 493 SNI dan standar khusus yang terdiri dari klaster teknologi dan pengujian, pengelolaan hutan, produk, dan standar khusus.
3. Jaringan kerjasama kegiatan litbang di dalam negeri yaitu dengan pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat. Sedangkan dengan luar negeri antara lain Asia Tenggara-ASEAN, CIFOR, ICRAF, ACIAR, IUFRO, IRP-UNEP, UNFF, AfoCO, Komatsu, World Bank, USAID, dan APFNet.
4. Hasil-hasil litbang sebanyak 983 topik hasil-hasil riset, serta 5.195 produk ilmiah, pengkajian untuk penyusunan standardisasi seperti kajian kualitas lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, resolusi konflik, pengolahan hasil hutan, keteknikan hutan, ekonomi dan industri kehutanan, konservasi SDH, peningkatan nilai jasa lingkungan, konservasi sumberdaya air, obat herbal tanaman hutan, hasil hutan bukan kayu, pengelolaan DAS, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Menurut Bulu dan Sujono (2021), seorang penyuluh dalam menjalankan tugasnya berinteraksi dengan para peneliti sebagai penghasil atau sumber teknologi dan inovasi dan sararan utama yang meliputi pelaku utama (petani dan keluarganya) dan pelaku usaha (pebisnis) sebagai pengguna teknologi dan inovasi di lapangan. Penyuluh kehutanan di sini adalah sumber informasi teknologi dan inovasi yang dikemas dengan bahasa popular dengan metode yang mudah diterima oleh sasaran utama dalam kegiatan penyuluhan. Para penyuluh kehutanan sebanyak 41 orang yang tergabung dalam BSILHK dari Pusat,
Balai Besar, dan Balai adalah eks peneliti atau teknisi, sehingga mereka memiliki dua modal atau dwi tunggal dalam tugasnya. Hal ini tentu menjadi modalitas untuk menjalankan tugasnya sebagaimana yang tertuang dalam Permen LHK 3/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka siap untuk berkontribusi sesuai tupoksinya dalam usaha-usaha di sektor lhk yang dijabarkan dalam enam klaster, 38 sub klaster berusaha. Adapun enam klaster tersebut adalah: (1) Pemanfaatan hutan; (2) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; (3) Pengelolaan air limbah; (4) Pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi; (5) Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; serta (6) Perbenihan tanaman hutan. Dengan kata lain, para penyuluh kehutanan di BSILHK diharapkan berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.
Transisi kelembagaan dari BLI ke BSILHK berpengaruh terhadap struktur organisasi dan kesiapan SDM yang beralih jabatan dari peneliti/teknisi menjadi penyuluh kehutanan sehingga kemandirian dan motivasi diri para penyuluh kehutanan untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme melalui pelatihan dasar/teknis yang difasilitasi oleh KLHK. Fasilitasi dalam menjalankan tugasnya dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengembangan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyuluhan kehutanan. Penyuluh berasal dari kata suluh, yang berarti obor yang berfungsi sebagai “penerang” semua stakeholder pengelolaan hutan Indonesia dan usaha-usaha di sektor LHK. Harapan Menteri LHK terhadap badan baru ini agar tidak hanya memproduksi standar, namun juga dapat memastikan standar yang sudah ada dapat diimplementasikan para pelaku-pelaku usaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
Pada era digital, salah satu peran penyuluh kehutanan adalah melakukan upaya penguatan narasi di media-media standardisasi BSILHK, sekaligus dapat menghasilkan angka kredit untuk kepentingan karier profesionalnya.
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
36
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
Penyuluh kehutanan BSILHK merupakan eks peneliti dan teknisi dan sekarang beralih tugas sebagai penyuluh (sumber informasi teknologi dan inovasi) diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan pengendalian lingkungan hidup dan kehutanan dalam akselerasi pertumbuhan investasi dan usaha melalui intervensi standardisasi instrumen lingkungan hidup dan kehutanan.
Catatan Akhir
Berdasarkan uraian tulisan ini yang mengangkat peran penyuluh kehutanan dalam memperkuat BSILHK di era standardisasi ini, maka ada beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:
1. Kegiatan penyuluhan kehutanan meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyuluhan kehutanan. Penyuluh kehutanan yang tersebar di Pusat, Balai Besar dan Balai lingkup BSILHK sebanyak 41 orang perlu mendapatkan dukungan agar mampu berkontribusi dalam menyediakan, mengembangkan, menguatkan standar instrumen bidang LHK. Kegiatan penyusunan programa penyuluhan kehutanan tingkat UPT KLHK difasilitasi oleh unit kerja masing-masing dan pengesahannya dilakukan Kepala UPT KLHK. Programa ini sangat penting karena sebagai pedoman bagi penyuluh kehutanan dalam melaksanakan penyuluhan kehutanan pada tahun berjalan.
2. Peran penyuluh kehutanan adalah sumber informasi teknologi dan inovasi yang dikemas dengan bahasa populer dengan metode yang mudah diterima oleh sasaran utama dalam kegiatan penyuluhan kehutanan. Penyuluh kehutanan sebagai salah satu ujung tombak BSILHK, terutama pada era digital perlu melakukan penguatan narasi di media-media standardisasi BSILHK, sekaligus dapat menghasilkan angka kredit untuk kepentingan karier profesionalnya. Para penyuluh kehutanan BSILHK diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan Pengendalian lingkungan hidup dan kehutanan dalam akselerasi pertumbuhan investasi dan usaha melalui intervensi standardisasi instrumen lingkungan hidup dan kehutanan”.
Daftar Pustaka
Anonim. 2022. Draf Rencana Strategis Tahun 2022-2024 Badan Standarisasi dan Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Bulu, Y.G. dan Sujono. 2021. Tantangan Penyuluh Pertanian dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Menuju Pembangunan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern. Impulse. Yogyakarta.
Hariadi, S.S. 2021. Dinamika Penyuluhan dan Ilmu Penyuluhan Pertanian. Impulse. Yogyakarta.
Hariadi, S.S. dan Subejo (editor). 2021. Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Perspektif Teoritis dan Praktis. Impulse. Yogyakarta.
Kementerian LHK. 2019. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan.
Kementerian LHK. 2020. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan.
Kementerian LHK. 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kementerian Sekretariat Negara. 2020. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Slameto dan Adriyani, F.Y. 2021. Digitalisasi Penyuluhan dalam Perspektif Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat. Impulse. Yogyakarta.
37
URGENSI KAJI ULANG REGULASI BAKU MUTU TIMBAL (Pb)
Rita MukhtarPusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup. Email: [email protected]
Instrumen lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah
daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Salah satu instrumen lingkungan hidup adalah Baku Mutu (BM) lingkungan hidup, disamping 16 (enam belas) instrumen lingkungan hidup lainnya yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu tata ruang, analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), izin lingkungan, KLHS, UKL-UPL, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, pengawasan kepatuhan, penegak hukum, dan peran serta/keterlibatan masyarakat. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
Tercemar atau tidaknya suatu media lingkungan dilihat dari baku mutunya. Dalam baku mutu terdapat jenis dan nilai parameter. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur baku mutu lingkungan, di antaranya baku mutu udara ambien. Jenis parameter baku mutu udara ambien adalah sulfur dioksida (SO2), karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO2), oksidan fotokimia (Ox) sebagai Ozon (O3), Hidrokarbon Non Metane (NMHC), TSP,
PM10, PM2,5, dan timbal (Pb). Nilai baku mutu angka yang tertera pada baku mutu tersebut. Penyusunan dan penetapan baku mutu udara ambien ditetapkan dengan pertimbangan hasil inventarisasi udara dan aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan lingkungan. Artikel ini bertujuan membangun kesadaran bersama bahaya timbal terhadap kesehatan dan mendesaknya kaji ulang regulasi baku mutu polutan timbal (Pb).
Mengenal Baku Mutu Timbal
Peran saintis dalam menentukan jenis dan nilai parameter baku mutu sangat diperlukan, sehingga baku mutu benar-benar menjadi instrumen lingkungan hidup yang dapat mengendalikan pencemaran lingkungan hidup. Hasil inventarisasi udara dapat diperoleh dari beberapa hasil penelitian dan pemantauan kualitas udara ambien yang dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah, swasta, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hasil yang disampaikan bisa jadi dalam bentuk laporan, jurnal, atau policy brief yang perlu dikemas dalam bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pemangku kebijakan. Data yang diperoleh tentu akan beragam karena metode, alat, lokasi sampling serta tujuan dari masing-masing kegiatan yang berbeda-beda, hal ini akan menjadi tantangan dalam merumuskan nilai baku mutu lingkungan.
Setelah baku mutu ditentukan, nilai baku mutu perlu ditinjau ulang minimal 5 tahun sekali. Contohnya Baku mutu timbal (Pb) di udara ambien sudah berjalan selama 22 tahun sejak keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor: 41/1999 tentang pengendalian pencemaran
Salah satu tugas BSILHK adalah melakukan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dengan fungsi menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis rencana dan program perumusan dan pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Tentunya hal ini dapat dilakukan terhadap penilaian dan peningkatan standar baku mutu lingkungan dalam hal ini baku mutu timbal (Pb) di udara ambien dan parameter lainnya.
IDE & OPINI
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
38
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
udara. Hingga keluarnya PP 22/2021, nilai baku mutu timbal (Pb) di udara ambien masih tetap 2 µg/Nm3. Sementara WHO sudah mengatur baku mutu Pb nya menjadi 0,5 µg/Nm3, EPA juga telah merevisi baku mutu Pb di dalam TSP menjadi 0,15 µg/Nm3. India telah mengatur baku mutu harian Pb berdasarkan 3 kriteria yaitu untuk sensitif area yaitu 0,75 µg/Nm3, daerah industri 1,5 µg/Nm3, pemukiman dan perkotaan 1 µg/Nm3, dan baku mutu tahunannya 0,5-1 µg/Nm3. Negara Vietnam, Banglades, Nepal, Korea, Australia, Inggris, Amerika, pada umumnya telah mengatur baku mutu Pb tahunannya dibawah 0,5 µg/Nm3. Nilai baku mutu tersebut lebih rendah dari baku mutu Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa di Indonesia ditemukan aktifitas yang menyumbangkan keberadaan timbal di udara ambien seperti daur ulang aki bekas yang dilakukan secara ilegal skala kecil (home industry). Menurut Ahmad Safrudin, Direktur eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Used Lead Acid Battery (ULAB) atau daur ulang aki bekas illegal tersebar di kota/kabupaten seperti Tangerang, Bogor, Medan, Pekanbaru, Batam, Palembang, Lampung,Tangerang, Jakarta, Bekasi, Tegal, Lamongan, Pasuruan, Klaten, dan lain-lain [KPBB, 2021] .
Hasil pemantauan dan kajian timbal serta unsur logam berat lainnya di udara ambien di Serpong dan 16 kota lainnya telah dilakukan oleh PSIKLH (ex.PUSARPEDAL) kerjasama dengan Pusat Sain dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT) - BATAN Bandung sejak 2008 sampai 2010. Hasil penelitian karakteristis sumber pencemar berdasarkan unsur kimia yang ada di udara ambien menyimpulkan bahwa pencemaran Pb di Serpong berasal dari kegiatan pengolahan aki bekas. Pemantauan Pb dan logam berat lainnya di Serpong masih terus dilakukan hingga saat ini, dan sudah berkembang di 16 lokasi lainnya. Hasil yang diperoleh dapat menjadi early warning adanya suatu pencemaran, sehingga dapat dirumuskan strategi yang tepat agar kerugian yang lebih besar dapat dihindarkan.
Hasil survai ke lapangan yang menemukan pembakaran aki bekas yang dilakukan secara berpindah-pindah oleh sekelompok orang khususnya di Parung Panjang (Bogor), Pasar Kemis (Tangerang), dan Cinangka-Bogor.
Timbal, Polutan Udara Berbahaya Bagi Kesehatan
Berdasarkan hasil penelitian PSIKLH (ex. P3KLL-BLI) tahun. 2016 terhadap kadar Pb dalam darah anak-anak di Tangerang, Medan dan Lamongan terdapat perbedaan nilai, dimana konsentrasi tertinggi terdapat di Tangerang mencapai 59 µg/dL, dengan rerata 32,0 ug/dL, kadar Pb di Medan 11,46 µg/dL, rerata 4,38 µg/dL. Kegiatan ini dilakukan atas kerjasama P3KLL, KPBB dan FKMUI. Konsentrasi Pb dalam darah anak-anak di Tangerang sudah mencapai 7 kali dari nilai rujukan Centers for Disease Control and Prevention (CDC) yaitu 5 µg/dL. CDC adalah Pusat Pengendalian dan Penyakit Badan Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat Amerika Serika yang berfungsi untuk meningkatkan kesehatan dan keamanan publik dengan menyediakan informasi kesehatan, dan mempromosikan kesehatan dengan departemen kesehatan negara dan organisasi lainnya (Hindratmo. 2018).
Dampak pencemaran Pb terhadap kesehatan yaitu dapat menurunkan tingkat intelegensi anak. Berdasarkan penelitian WHO peningkatan kadar Pb dalam darah sebanyak 10 µg/dL pada anak-anak akan mengakibatkan penurunan IQ (intelligence quotient) sebesar 2.5 poin. Partikulat yang berukuran kurang dari 2.5 µm (PM2.5) apabila terhirup manusia dapat menembus bagian terdalam dari paru-paru dan akan menyebabkan masalah kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), kanker paru-paru, penyakit jantung dan banyak penyakit baru yang berhubungan dengan polutan. Konsentrasi Pb yang diukur pada penelitian ini berada pada ukuran PM2.5 nilainya sudah ada yang mencapai 2 µg/Nm3. Salah satu hasil penelitian menunjukkan nilai tertinggi konsentrasi Pb pada PM2.5 mencapai 2 ug/m3, sehingga perlu medapat perhatian karena melebihi baku mutu yang ditetapkan. Telah terbukti secara medis bahwa partikel matter (PM) halus (<2,5 mikrometer) mempunyai kontribusi besar terhadap kematian yang disebabkan oleh polusi udara yang berhubungan dengan kesehatan (Santoso et.al, 2011).
39
Gambar 1. Foto kegiatan pembakaran aki bekas di Parung Panjang-Bogor
Mitigasi Polutan Timbal
Pada tahun 2012 Pusarpedal, BATAN, dan KPBB melakukan pemantauan Pb di Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Hasil yang diperoleh menunjukkan kandungan logam berat Pb pada PM2,5 sudah mencapai konsentrasi 2,66 µg/Nm3. Kegiatan daur ulang aki bekas dilakukan dengan menggunakan tungku yang dilengkapi dengan alat untuk mengendalikan pencemaran udara, namun hasil yang diperoleh kurang optimal sehingga kegiatan tersebut ditutup sementara hingga ditemukan teknologi yang perlu dilakukan perbaikan baik dari teknologi peleburan dan sarana prasarana yang digunakan. Pemahaman terkait hal ini perlu terus disosialisasikan ke masyarakat yang melakukan kegiatan peleburan aki bekas.
Beberapa policy recommendation langkah cepat untuk perbaikan pengelolaan aki bekas disampaikan oleh Ahmad Safrudin (KPBB) dalam workshop “Mencegah dan Memantau Pencemaran Timbel (Pb) di Indonesia” yang diselenggarakan pada 23 Maret 2022 secara virtual di antaranya:
1. Perlu menyelenggarakan rapat koordinasi teknis (rakornis) pengelolaan aki bekas dengan mengundang perusahaan-perusahaan pelebur berizin untuk memetakan rantai pasok berizin mereka yang mencakup transporter, pengumpul dan pengumpul sementara (dropping poin) dengan cara peningkatan kapasitas dan legalisasi rantai pasok berizin, mengkondisikan (conditioning) pelaksanaan
penegakan hukum secara ketat, koordinasi mengefektifkan pengelolaan aki bekas, serta merencanakan pemantauan semua kegiatan yang dilaksanakan;
2. Mengeluarkan surat edaran agar para Bupati/Walikota untuk melaksanakan bimbingan teknis proses legalisasi dropping poin, pengumpulan skala Kabupaten/Kota dan pengumpul serta transporter aki bekas dalam kerangka legalisasi rantai pasok aki bekas sesuai dengan kewenangan dan tugas, pokok, fungsi;
3. Melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal pajak Kementerian Keuangan untuk menerangkan tax amnesty dalam proses legalisasi dropping poin aki bekas.
Dan beberapa rencana aksi yang disampaikan Ahmad Safrudin di antaranya reformulasi regulasi, peran aktif produsen aki baterai/aki, larangan jual beli aki bekas secara ilegal/di luar tata kelola yang ditetapkan, tindak keras pelanggar tata kelola aki bekas, pendataan peredaran aki bekas, perlu fasilitas pertemuan untuk solusi terbaik, peran pabrik aki, legalisasi rantai pasok, peleburan komunal, riset mendalam baik dalam tata kelola aki bekas (aspek ekonomi) maupun dampak (lingkungan, kesehatan dan sosial) serta yang tak kalah pentingnya adalah menghentikan sumber pencemar dengan mendorong kepatuhan pengelolaan daur ulang aki bekas sesuai regulasi melalui pengawasan yang ketat dan pembinaan menuju internalisasi biaya dampak (eksternality cost), agar diserap
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
40
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
Gambar 2. Tungku Peleburan aki bekas di Lamongan
ke dalam cost structure pengelolaan aki bekas. Hal lain yang perlu ditinjau terhadap baku mutu udara ambien adalah jenis parameter baku mutu khususnya untuk logam berat yang tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah nomor: 22 tahun 2021 hanya memuat parameter logam berat timbal (Pb). Masih banyak logam berat lainnya yang berbahaya bagi kesehatan manusia yang perlu dimasukkan, diantaranya kadmium (Cd), arsen (As), merkuri (Hg), kromium (Cr), mangan (Mn), dan nikel (Ni). Beberapa negara telah memasukkan parameter logam berat pada baku mutu udara ambien seperti Australia (Pb, Cd, As, Mn, Hg, V), Vietnam (Pb, Cd, Mn, Hg, As, Ni, Cr6+), serta Washington DC (Pb, Cd, As, Cr).
BSILHK dan Upaya Standardisasi Polutan Timbal
Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) dalam Rencana strategis (Renstra) 2022-2024 menyatakan bahwa persoalan lingkungan hidup tidak dapat lagi direspon dengan orientasi sukarela. Faure dan Partain (2019) menyatakan ketidakpatuhan terhadap standar biasanya dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana. Karena dalam kasus khusus aktor tidak bebas memilih langkah-langkah yang ingin mereka gunakan, untuk mencapai hasil yang optimal kualitas lingkungan, pendekatan ini oleh para ekonom sering disebut sebagai pendekatan atur dan awasi (command and control). Salah satu tugas BSILHK adalah melakukan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dengan fungsi menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis rencana dan program perumusan dan pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Tentunya hal ini dapat dilakukan terhadap penilaian dan peningkatan standar
baku mutu lingkungan seperti baku mutu timbal (Pb) di udara ambien dan parameter lainnya.
Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan (PSIKLH) merupakan salah satu pusat yang mendukung tugas, pokok dan fungsi BSILHK yang dengan penyediaan dan pembaharuan (updating) standar instrumen kualitas lingkungan hidup.
Kelembagaan BSILHK dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki tata hubungan dengan internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian/Lembaga (K/L) lain yang memiliki peran dalam penyusunan standar. Tata hubungan kerja antara BSILHK dengan lembaga atau satuan kerja di lingkungan internal maupun eksternal KLHK menggambarkan adanya keterkaitan kewenangan dari BSILHK dengan lembaga-lembaga lain. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dilandaskan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK. Keterkaitan kewenangannya meliputi perencanaan, perumusan, penetapan, penerapan/implementasi standar instrumen LHK, kontrol/pengawasan dan pengembangan. (Renstra BSILHK, 2022).
Catatan Akhir
Kualitas lingkungan menentukan kualitas hidup manusia. Semakin baik kualitas udara dan air akan meningkatkan kualitas kesehatan manusia. Geliat pertumbuhan ekonomi yang mendorong terjadinya industrialisasi menyebabkan pencemaran udara. Timbal (Pb) merupakan salah satu polutan udara berbahaya yang berasal dari industri daur ulang aki. Bahkan kadar timbal sebesar 10 µg/dL dalam darah anak-anak berakibat penurunan daya intelegensia sebesar sebesar 2.5 poin. Sedangkan partikulat
41
timbal dengan ukuran < 2.5 µm (PM2.5) dapat menembus bagian terdalam dari paru-paru dan menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), Ironisnya, regulasi pengendalian pencemaran udara yang ada belum disesuaikan dengan dinamika perkembangan jaman. Dimana toleransi baku mutu Timbal di Indonesia masih pada kisaran 2 µg/Nm3. Sedangkan, lembaga kesehatan dunia (WHO) telah merevisi baku mutu timbal (Pb) nya menjadi 0,5 µg/Nm3, Tentu, kaji ulang baku mutu Timbal di Indonesia mendesak dilakukan dengan pertimbangan dampak kesehatan yang ditimbulkannya. Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan (PSIKLH) sebagai bagian dari BSILHK perlu mengawal review baku mutu polutan Timbal (Pb) untuk menjaga kualitas udara di Indonesia lebih baik dimasa mendatang. Sekian.
Daftar Pustaka
Aminudin, C. (2012). Perkembangan Pengaturan Kualitas Udara di Indonesia: dari Pendekatan Tradisional Atur dan Awasi ke arah Bauran Kebajikan. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 3(1), 1–29. https://doi.org/10.38011/jhli.v3i1.39
Faure, Michael G., dan Roy A. Partain. 2019. Environmental Law and Economics Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
Hindratmo, (2018). Kadar Timbel Dalam Darah Siswa Sekolah Dasar Di Sekitar Peleburan Aki Bekas Di Kabupaten Tangerang dan Lamongan.Jurnal Ecolab Vol 12. No.2 2018. http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JKLH/article/view/4933/4377
Rencana Strategis Tahun 2022-2024 Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan-KLHK, 2022.
Safrudin, A. (2021). Pencegahan dan Pemantauan Pencemaran Timbel di Indonesia, Virtual National workshop, 23 Maret 2022, Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB).
Santoso, M, Lestiani, D.D., Mukhtar, R., Hamonangan, E., Syafrul, H., Markwitz, A., Hopke, P.K. (2011). Preliminary study of the sources of ambient air pollution in Serpong, Indonesia. Atmos. Pollution Res. 2, 190–196. https://doi.org/10.5094/APR.2011.024
U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) (2019). Integrated Science Assessment (ISA) for Particulate Matter, Report No. EPA/600/R-19/188, Center for Public Health and Environmental Assessment Office of Research and Development U.S. Environmental Protection Agency Research Triangle Park, NC, December 2019.
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
42
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
GREEN COMPUTING, STRATEGI TIK RAMAH LINGKUNGAN DI IBU KOTA NEGARA
Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur telah di mulai, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga memastikan bahwa konsep pengembangan teknologi informasinya menggunakan sistem smart city. Konsep ini membuat seluruh aspek teknologi, informasi dan komunikasi dapat di akses secara bersama dan bersifat masif. Pemerintah, dalam hal ini Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus dapat memastikan bahwa pengembangan infrastruktur dan penggunaan perangkat pada smart city nanti harus terstandardisasi dalam kerangka green computing untuk mendukung teknologi informasi dan komunikasi yang ramah lingkungan.
Pesatnya perkembangan teknologi telah mengganti gaya hidup manusia yang awalnya beraktifitas secara konvensional, saat ini hampir seluruhnya terbantu oleh teknologi digital. Beragam kegiatan mulai dari pencarian informasi, membaca berita, belanja, transaksi perbankan, pekerjaan perkantoran berbasis awan, menyimpan data pribadi maupun pekerjaan, dan pemesanan transportasi kini dilakukan dengan bantuan teknologi digital. Masifnya transformasi digital akan semakin nyata, hal ini ditandai dengan adanya kebijakan pemerintah berbasis digital di masa pandemi ini dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia.
Tidak hanya itu, layanan publik, proses bisnis di perusahaan, sampai usaha rumahan juga mulai merambah teknologi digital. Dampak masifnya digitalisasi akan membuat setiap perusahaan hingga instansi dari berbagai lini memerlukan penyimpanan data yang mumpuni. Teknologi
penyimpanan data tersebut biasanya berbentuk data center atau juga cloud computing.
Server data center seyogyanya berjalan dengan kondisi up-time 24 jam. Dilansir dari Kompas Tekno, menurut US Environmental Protection Agency pada tahun 2010 saja, energi yang digunakan untuk menggerakkan data center di seluruh dunia pertahunnya lebih besar daripada energi listrik yang dipakai 10 juta rumah setiap tahun.
Pada hasil studi tersebut juga diperoleh informasi yang menarik. Studi tersebut menyebutkan, bahwa data center menyebabkan polusi berupa emisi karbon dioksida sebesar lebih dari 70 juta ton. Jika dilakukan komparasi dalam rangka menghilangkan dampak polusinya, maka diperlukan sekitar dua miliar pohon. Tingginya angka emisi tersebut diperoleh dari energi yang digunakan pada mesin pendingin, disusul oleh penggunaan perangkat lainnya seperti peralatan komputer, peralatan komunikasi, dan jaringan.
Seperti kita ketahui untuk menjalankan proses digitalisasi, penggunaan fasilitas data center hingga sistem cloud computing sudah dapat dipastikan akan menjadi andalan semua pihak yang terlibat. Kinerja data center yang besar dimana terdapat penampungan data dan informasi digital, biasanya didukung daya listrik yang besar, hal ini secara tidak langsung akan menyumbang emisi karbon yang berdampak pada kelestarian lingkungan.
Dalam laporan Nature.com, dunia TI secara menyeluruh menyumbang 2 persen total emisi gas rumah kaca. Untuk data center sendiri turut menyumbang 0,3 persen emisi karbon ke udara dan menyebabkan pemborosan listrik. Sumber
“Mengupayakan green computing agar berhasil akan sulit apabila tidak melibatkan dan mendapat dukungan dari berbagai pihak (pengembang, pemerintah, maupun pengguna). Green computing akan berhasil apabila perilaku pengguna TIK selaras dengan tujuan green computing. Apabila perilaku pengguna TIK telah terbentuk, maka tingkat keberhasilan green computing akan jauh lebih besar”.
Muhamad Sahri ChairPranata Komputer Ahli MudaSekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK. E-mail: [email protected]
IDE & OPINI
43
terbesar konsumsi listrik tersebut terdapat pada proses pendinginan server yang ada di dalamnya. Total 40 persen dari total energi listrik yang digunakan.
Menilik penggunaan energi data center yang sangat boros untuk penggunaan energi yang terlalu banyak, hal ini menjadi fokus utama untuk pendukung keberhasilan green computing. Data center dapat menjadi potensi dalam meningkatkan energi dan efisiensi ruangan melalui teknik seperti konsolidasi penyimpanan dan virtualisasi. Banyak organisasi mulai menghilangkan server yang kurang bermanfaat, dimana hasilnya adalah pengurangan penggunaan energi. Sebagai contoh, sejak tahun 2011, Pemerintah Pusat Amerika Serikat telah memiliki minimal 10% target pengurangan energi dari pusat data. Lalu Google Inc., telah membuat inovasi teknologi pendingin evaporasi yang sangat efisien berhasil mengurangi penggunaan energi sebanyak 50%.
Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) sudah mulai mencermati hal ini. Melihat besarnya antusiasme penggunaan layanan digital dan penyimpanan data di data center, BSILHK sepertinya perlu mengagendakan dan mempertimbangkan adanya standardisasi penggunaan teknologi informasi data center serta perangkat TIK lainnya yang ramah lingkungan dalam kaitannya mendukung pembangunan smart city di Ibu Kota Negara Nusantara. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka menyelaraskan penggunaan teknologi informasi ramah lingkungan, di antaranya dengan menerapkan green computing.
Menurut informasi di laman binus.ac.id, green computing adalah suatu cara tentang bagaimana kita menggunakan sumber daya komputer atau perangkat elektronik yang kita miliki secara efisien dan ramah lingkungan. Green computing menyasar bagaimana upaya kita dalam memanfaatkan teknologi informasi tetapi juga ikut melestarikan seluruh kehidupan yang ada di bumi.
Tujuan green computing yaitu untuk mengurangi penggunaan bahan yang dampaknya berbahaya untuk lingkungan, efisiensi penggunaan energi, penyeimbang antara teknologi dan lingkungan agar tercipta suatu teknologi yang ramah lingkungan, tidak merusak alam atau lingkungan hidup serta menerapkan daur ulang pada bahan-bahan pembuat komputer.
Green computing menarik untuk dibahas lebih jauh, terutama dalam konteks memberikan
dukungan dalam pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur. Laman kompas.com memberitakan bahwa saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi berteknologi 5G. Hal ini untuk mendukung konsep smart city yang akan dibangun di IKN. Konsep smart city IKN akan menghubungkan seluruh area di IKN dan mengatasi masalah tertundanya layanan telekomunikasi.
Sementara itu dikutip dari laman Kemenkominfo, dalam rangka menerapkan smart city, terdapat beberapa unsur yang perlu dikembangkan, yaitu smart government. Smart government mengusung konsep pelibatan salah satu unsur penting perkotaan, yaitu pengembangan badan/instansi pemerintahan berdasarkan fungsi teknologi informasi. Tujuan TIK agar dapat diakses pihak terkait yang berkepentingan secara efektif dan efisien. Prinsip dasar smart government yang dijadikan acuan dalam penerapan smart city, yaitu:
1. Mengolaborasikan dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat.
2. Mengembangkan operasional agar lebih efisien.
3. Meningkatkan manajemen organisasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur.
4. Membuat sistem basis data yang dapat diakses secara umum.
5. Mengolah informasi data yang up to date (real time).
6. Menggunakan teknologi yang mutakhir.7. Adanya koordinasi antara stakeholders.
Dilansir dari kompas.com, visi pembangunan smart city IKN adalah dalam rangka menciptakan kesatuan kota hijau (green city) yang berdaya saing dan berbasis teknologi didukung sinergi smart economy, smart people, smart government, smart mobility, dan smart living.
Melihat dari acuan penerapan smart city, maka secara linier sudah dapat dipastikan penggunaan sumber daya juga akan semakin besar. Akan banyak fasilitas-fasilitas pusat data yang dibangun, perangkat elektronik yang terhubung, dan alat-alat pandukung lainnya yang dikhawatirkan akan meningkatkan emisi karbon dan berdampak pada kelestarian lingkungan. Disinilah prinsip green computing perlu berjalan beriringan dengan green city. Apabila hal ini diterapkan di IKN tentu akan membuat lingkungan menjadi lebih baik. Pengelolaan perangkat komputer dan infrastruktur yang dibangun di green city IKN harus memahami konsep dasar dari green computing. Apabila
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
44
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
konsep green computing terpenuhi, maka diharapkan kondisi lingkungan di IKN akan menjadi lebih baik.
Untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari green computing di smart city IKN maka perlu diperhatikan 3 (tiga) indikator, sebagai berikut:
1. Meningkatkan efisiensi energi dengan mengurangi jejak karbon.
2. Mengurangi penggunaan barang elektronik.3. Melakukan perubahan terhadap gaya
hidup dengan dampak yang rendah untuk lingkungan.
Strategi dari green computing yang dapat mengurangi pembuangan dari zat karbon, seperti menggunakan virtualisasi untuk mengurangi jumlah server, menggunakan virtualisasi untuk mengurangi tenaga dan pembuangan kebutuhan dari desktop, mengganti sistem paper base dengan sistem komunikasi daring, dan lain lain.
Sementara itu, pendekatan prinsip green computing, dapat dilakukan melalui cara:
1. Green use: Meminimalkan konsumsi listrik perangkat komputer dalam cara yang ramah lingkungan.
2. Green disposal: membuat kembali komputer yang sudah ada atau mendaur ulang perangkat elektronik yang tidak digunakan.
3. Green design: Merancang komputer yang hemat energi, server, printer, proyektor dan perangkat digital lainnya.
4. Green manufacture: Meminimalkan limbah selama proses pembuatan komputer dan mengurangi dampaknya terhadap lingkungan.
Dari pembahasan di atas, keberhasilan green computing dapat dilihat dari 4 (empat)
perspektif, yaitu Dimensi Kerja, Tingkatan Area Kerja, Metode, dan Stakeholders.
Selain melihat dari empat perspektif seperti pada tabel di atas, pemerintah melalui BSILHK atau pihak terkait yang berwenang harus turut aktif memproklamirkan konsep green computing dengan melakukan beberapa program serta membuat peraturan-peraturan untuk menegakkannya. Di sini standardisasi menjadi penting, karena tanpa adanya kepatuhan dalam menjalankan green computing, maka kontribusi terhadap peningkatan emisi karbon tetap akan tinggi. Yang akhirnya nanti dikhawatirkan akan menghambat pembangunan smart city yang telah dijalankan pemerintah.
Mengupayakan green computing agar berhasil akan sulit apabila tidak melibatkan dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak mulai dari pihak pengembang, pemerintah, hingga pengguna, baik individu, kelompok, maupun korporasi. Green computing akan berhasil apabila perilaku pengguna TIK telah selaras dengan tujuan green computing. Apabila perilaku pengguna TIK telah terbentuk, maka tingkat keberhasilan green computing akan jauh lebih besar.
BSILHK perlu melakukan kajian lebih dalam secara ekstensif, untuk memperoleh gambaran atau analisa sejauh mana kontribusi TIK membentuk perilaku masyarakat supaya peduli kepada lingkungan. Apakah teknologi dapat mengubah perilaku penggunanya dan mencari jawaban kenapa kita harus menggunakan teknologi untuk mengubah perilaku individu, kelompok, dan pemerintah untuk berperilaku lebih hijau.
No. Perspektif Keterangan
1. Dimensi Kerja Dimensi Kerja adalah besaran jika green computing dijalankan akan mengubah nilai dari besaran-besaran tersebut. Besaran ini merupakan sesuatu yang diupayakan diubah oleh green computing untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan. Dimensi-dimensi ini saling terhubung satu sama lain, di mana perubahan di dimensi yang satu akan menjadikan peningkatan atau pengurangan di dimensi lainnya. Dengan kata lain, setiap solusi yang diberikan biasanya memiliki kelemahan (drawbacks). Beberapa dari dimensi tersebut antara lain, waktu, energi, biaya, dan dampak negatif terhadap lingkungan.
2. Tingkatan Area Kerja
Green computing sebagai usaha praktis dalam menjawab tanggung jawab lingkungan dapat bekerja pada tataran area kerja (levels of working area) yang berbeda-beda.
Dari tataran efisiensi kinerja fisik (hardware), optimasi algoritma (software), rekayasa ulang proses bisnis, kebijakan dan aturan (governance), hingga kepada pembentukan perilaku (behaviour)
45
No. Perspektif Keterangan
3. Metode Dari kajian literatur diperoleh bahwa green computing berkerja dengan mengurangi (reduce), guna ulang (reuse), daur ulang (recycle), optimisasi (optimization), virtualisasi (virtualization), pengukuran (measuring), memberikan informasi (informing), dan memberikan pengetahuan (creating knowledge).
4. Stakeholders Stakeholders adalah setiap pihak yang terlibat atau menjadi pelaku atau objek dari green computing. Stakeholders dapat berupa individu, kelompok, masyarakat, vendor sebagai produsen ICT, pelanggan sebagai pemakai ICT, atau pun pemerintah sebagai regulator. Stakeholders pun dapat berupa bidang ICT, bidang bisnis, bidang pemerintahan, dan sebagaian dari ekosistem. Oleh karena itu, Green computing tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari suatu ekosistem yang memiliki subsistem-subsistem yang terkait satu sama lain
Gambar 1. Empat perspektif Green Computing
Daftar Pustaka
Alfianz Vergié. (2015). GREEN_COMPUTING. https://www.academia.edu/10930884/GREEN_COMPUTING
Fathia Yasmine. (2020, July 15). Data Center Sumbang Emisi Karbon dan Boros Listrik, SpaceDC Punya Solusinya. Infokomputer.Grid.Id. https://infokomputer.grid.id/read/122243450/data-center-sumbang-emisi-karbon-dan-boros-listrik-spacedc-punya-solusinya?page=all
Intan Rakhmayanti Dewi. (2022, January 20). Dukung Penerapan Smart City di Ibu Kota Baru, Kominfo Siapkan Infrastruktur Telekomunikasi 5G. Inews.Id. https://www.inews.id/techno/telco/dukung-penerapan-smart-city-di-ibu-kota-baru-kominfo-siapkan-infrastruktur-telekomunikasi-5g
kompas.com. (2022, January 17). Apa Itu Smart City, Konsep yang Akan Dipakai di Nusantara, Ibu Kota Baru Indonesia. Kompas.Com. https://regional.kompas.com/read/2022/01/17/132814178/apa-itu-smart-city-konsep-yang-akan-dipakai-di-nusantara-ibu-kota-baru?page=all.
Sri Noviyanti, & Latief. (2015, March 28). “Data Center” Memang Boros Listrik, Ini Cara Menyiasati Supaya Hemat! Tekno.Kompas.Com. https://tekno.kompas.com/read/2015/03/28/08000027/.Data.Center.Memang.Boros.Listrik.Ini.Cara.Menyiasati.Supaya.Hemat.?page=all
Yohannis, A. (2010). Menuju Kerangka Kerja Green IT: Green IT dari Empat Perspektif.
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
46
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
MERENTAS JALAN PENGUATAN LITERASI BERSAMA PERPUSTAKAAN BPSILHK SOLO
Restrukturisasi birokrasi yang dilakukan pemerintah membuat beberapa perubahan dalam organisasi pemerintahan. Salah satu
lembaga yang mengalami perubahan yaitu: lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) termasuk didalamnya Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPPTPDAS). Hal tersebut terjadi sebagai jawaban pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pasal 48 (Republik Indonesia, 2019). Perubahan tersebut menuntut BP2TPDAS pecah menjadi dua dimana sebagian peneliti dan teknisi litkayasa beralih menjadi pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan sebagian peneliti, teknisi litkayasa, seluruh fungsional lain dan staf tetap berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berubah nama menjadi pegawai Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Solo (BPSILHK Solo).
Perubahan berdampak terhadap perpustakaan termasuk Perpustakaan Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Perpustakaan BP2TPDAS) dan berubah nama menjadi Perpustakaan Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Solo (Perpustakaan BPSILHK Solo) yang merupakan salah satu sarana prasarana yang dimiliki BPSILHK Solo. Sejak diberlakukannya PermenLHK RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perpustakaan BPPTPDAS otomatis juga berubah nama menjadi Perpustakaan BPSILHK Solo (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).
Perubahan tersebut menuntut perpustakaan untuk ikut berubah mengikuti perubahan lembaga yang menaunginya. Secara administrasi Perpustakaan BPSILHK Solo berada di bawah Subbagian Tata Usaha, tepatnya dalam kegiatan pengelolaan data dan informasi. Melihat dari tupoksi lembaga induknya, tugas dan fungsi perpustakaan mengalami perubahan drastis. Perpustakaan BPSILHK Solo mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas BPSILHK Solo dengan menyediakan koleksi dan informasi yang dimilikinya.
Perubahan dijadikan peluang dan semangat baru untuk terus berusaha dan berkarya. Salah satu kegiatan yang dilakukan Perpustakaan BPSILHK Solo adalah dengan melakukan literasi sampai ke tingkat tapak dengan memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui pembangunan Perpustakaan KHDTK Gombong.
Perpustakaan BPSILHK Solo termasuk dalam jenis perpustakaan khusus. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 mengenai Perpustakaan memaparkan perpustakaan khusus sebagai perpustakaan yang ditujukan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan lembaga lainnya (Republik Indonesia, 2007). Perpustakaan ini berada di komplek kantor BPSILHK Solo tepatnya di Jalan Jend. A. Yani, Pabelan, Kartasura PO BOX 265, Surakarta, 57102, telepon: (0274) 716709..
Tulisan ini membahas bagaimana Perpustakaan BPSILHK Solo merentas jalan menguatkan literasi sampai ke tingkat tapak. Kemudian, tulisan ini juga membahas Perpustakaan KHDTK Gombong secara sekilas.
Perpustakaan BPSILHK Solo akan terus berubah dan berusaha mengikuti perubahan yang terjadi di lembaga induknya. Perpustakaan juga berusaha bertransformasi untuk selalu menjadi lebih baik di masa sekarang dan akan datang tidak hanya sebagai pusat informasi dan koleksi namun juga menjadi penggerak literasi sampai ke tingkat tapak.
Amma NaningrumPustakawan Ahli MudaBalai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Solo. E-mail: [email protected]
IDE & OPINI
47
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
Rintisan Program Literasi Perpustakaan KHDTK Gombong
Perpustakaan KHDTK Gombong merupakan perpustakaan binaan BPSILHK Solo dan berdiri sebagai salah satu bentuk kerja sama antara Perpustakaan BPSILHK Solo dan Pemerintah Desa Somagede. Perpustakaan berlokasi di sekitar kawasan hutan tepatnya di Desa Somagede, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Desa ini berada di wilayah pegunungan dan hutan serta menjadi salah satu wilayah yang terisolasi. Akses kesehatan, air bersih, transportasi dan internet masih sulit. Fasilitas umum terdekat seperti pasar, rumah sakit, kantor pemerintahan jauh dari jangkauan.
Perpustakaan KHDTK Gombong diresmikan pada 17 November 2021 oleh Kepala BPSILHK Solo (Ir. Yoyok Sigit Haryotomo, M.M) dan Kepala Desa Somagede (Bapak Samsi) dan disaksikan oleh pegawai BPSILHK Solo, para perangkat desa, guru dan kepala sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat di Desa Somagede.
Perpustakaan KHDTK Gombong termasuk perpustakaan umum. Perpustakaan ini awalnya dikhususkan untuk anak-anak dan remaja tetapi dengan berjalannya waktu dan semakin beragamnya koleksi yang dimiliki perpustakaan ini juga bisa diakses dan dimanfaatkan untuk lapisan masyarakat lainnya. Perpustakaan didirikan sebagai bentuk kepedulian BPSILHK Solo untuk menguatkan literasi dan meningkatkan minat baca masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Tujuan Perpustakaan
Perpustakaan KHDTK Gombong didirikan dengan tiga tujuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 07/SET/PK/KUM.3/11/2021
dan Nomor 140/PKS/2021 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Perpustakaan di Kawasan Sekitar KHDTK Gombong (Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan DAS dan Kepala Desa Somagede, 2021). Tujuan perpustakaan tersebut yaitu untuk:
1. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan KHDTK sebagai kawasan hutan yang mampu berkontribusi dalam pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan hutan lestari dengan pembangunan perpustakaan.
2. Meningkatkan minat baca masyarakat di sekitar kawasan KHDTK Gombong.
3. Meningkatkan literasi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Literasi di sini diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca, menulis dan menggunakan bahasa lisan. Informasi melimpah di internet, tetapi tak semua informasi tersebut bermanfaat dan tepat untuk masyarakat. Selain itu, kondisi geografis dan kurangnya akses terhadap sumber informasi juga menjadi kendala terbesar bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan termasuk masyarakat Desa Somagede. Perpustakaan KHDTK Gombong didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.
Terdapat enam literasi dasar yang harus dimiliki dan dikuasai masyarakat Indonesia pada abad ke-21 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2017). Literasi tersebut yaitu yaitu:
a. Literasi baca-tulisLiterasi ini merupakan pengetahuan dan kecakapan dalam hal membaca dan menulis.
(a) (b)Gambar 1. Ruang koleksi (a), ruang baca dan diskusi Perpustakaan BPSILHK Solo (b)
48
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
Literasi ini berguna bagi masyarakat dalam mencari, menelusur, mengolah dan memahami informasi. Kemampuan tersebut digunakan untuk menganalisis, menanggapi dan menanggapi teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi dirinya dan untuk bisa berperan dalam lingkungan sosial masyarakat.
b. Literasi numerisasiLiterasi numerisasi berkaitan dengan kemampuan dan kecakapan seseorang dalam mengaplikasikan bilangan, memahami angka, simbol matematika dalam kehidupan.
c. Literasi sainsLiterasi sains berhubungan dengan kemampuan dan kecakapan seseorang dalam memahami pengetahuan dan kecakapan ilmiah, termasuk didalamnya pengetahuan mengenai lingkungan sekitar atau yang
disebut dengan literasi lingkungan. Dengan pengetahuan ini seseorang menjadi lebih sadar akan pentingnya lingkungan.
d. Literasi finansialLiterasi ini berkaitan dengan pengetahuan dan ketrampilan seseorang dalam mengelola sumber keuangannya secara efektif dan efisien. Literasi ini memberikan seseorang kemampuan untuk memahami dan memprioritaskan kebutuhannya berdasarkan skala prioritasnya. Alhasil literasi ini memberi kesejahteraan finansial bagi yang memilikinya.
e. Literasi digitalPerkembangan teknologi, komunikasi dan informasi saat ini sampai pada tahap dunia digital. Sebagian besar aspek dan bidang kehidupan sekarang ini tersedia dalam bentuk digital. Hal tersebut mengharuskan seseorang untuk belajar agar bisa memanfaatkannya teknologi tersebut.
f. Literasi budaya & kewargaanLiterasi budaya dan kewargaan merupakan literasi terakhir yang wajib dimiliki masyarakat Indonesia pada abad 21 ini. Literasi ini berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam memahami dan bersikap terhadap budaya Indonesia sebagai sebuah identitas bangsa.
Penguatan keenam literasi tersebut dilakukan Perpustakaan KHDTK Gombong melalui penyediaan koleksi yang sesuai. Dari keenam literasi tersebut, literasi sains khususnya literasi lingkungan menjadi isu dan prioritas utama Perpustakaan KHDTK Gombong. Harapannya
Gambar 2. Rombongan BPSILHK Solo sebelum dan saat berangkat ke lokasi
Gambar 3. Kegiatan Pengolahan koleksi Perpustakaan KHDTK Gombong
49
dengan penyediaan informasi dan koleksi yang berkaitan dengan literasi lingkungan, masyarakat khususnya sekitar kawasan hutan menjadi lebih mengenal lingkungan, sadar dan cakap dalam bertindak. Sehingga tindakannya selalu disesuaikan untuk memelihara, memulihkan dan meningkatkan kesehatan lingkungan.
1. Fungsi PerpustakaanPerpustakaan KHDTK Gombong memiliki fungsi sebagai tempat membaca dan rekreasi dengan penyediaan koleksi yang menghibur dan informatif. Selain itu, berfungsi sebagai tempat memperoleh informasi mengenai KHDTK Gombong, lingkungan hidup dan kehutanan melalui koleksinya.
Perpustakaan ini bisa menjadi wadah bagi masyarakat khususnya anak-anak dan remaja membaca dan belajar selama pandemi Covid-19. Membaca juga memberikan manfaat kepada pengunjung perpustakaan untuk lebih mengenal dunia lewat koleksi yang dimilikinya. Perpustakaan ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk lebih mengenal KHDTK Gombong, BPSILHK Solo, lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Koleksi PerpustakaanTerhitung sampai Januari 2022, Perpustakaan KHDTK Gombong memiliki jumlah koleksi sekitar 768 eksemplar dengan subjek yang berbeda-beda, seperti ilmu pengetahuan umum, ilmu, agama, lingkungan dan kehutanan. Koleksi yang dimiliki mayoritas berupa cerita pendek (cerpen), cerita bergambar (cergam), komik dan novel. Sebagian yang lain berupa buku teks, buku-buku agama, majalah dan sebagainya. Sebagian besar koleksi merupakan sumbangan dari perorangan dan balai di lingkungan lembaga kehutanan lainnya.
Koleksi diklasifikasi berdasarkan sistem DDC (Dewey Decimal Classification) dan ditambah dengan metode warna untuk memudahkan pengguna dan pengelola perpustakaan dalam menelusur informasi.
3. Sistem Layanan PerpustakaanSistem pelayanan terbuka diterapkan Perpustakaan KHDTK Gombong. Pengunjung bisa langsung menelusur koleksi dan membacanya. Saat ini, pencarian masih dilakukan secara manual dengan menelusur koleksi di rak atau melihat buku induk. Perpustakaan dikelola oleh salah satu perangkat desa yang bernama Ibu Mega. Pengunjung perpustakaan dapat memanfaatkan jasa layanan yang disedikan di perpustakaan.
a. Jenis LayananPerpustakaan menyediakan layanan sirkulasi berupa peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan. Selain itu, perpustakaan juga menyediakan layanan membaca koleksi di tempat.
b. Waktu LayananPerpustakaan KHDTK Gombong buka dari saat jam kerja Balai Desa Somagede yaitu Senin sd. Jum’at dari Jam 07.30-16.00 WIB.
Catatan Akhir
Perpustakaan BPSILHK Solo akan terus berubah dan berusaha mengikuti perubahan yang terjadi di lembaga induknya. Perpustakaan juga berusaha bertransformasi untuk selalu menjadi lebih baik di masa sekarang dan di masa mendatang. Tidak hanya sebagai pusat informasi dan koleksi tetapi sebagai bisa menjadi penggerak literasi sampai ke tingkat tapaksehingga masyarakat di sekitar kawasan hutan bisa mendapatkan akses
Gambar 4. Peresmian Perpustakaan KHDTK Gombong
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
50
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
terhadap informasi dan sumber informasi untuk meningkatkan indeks literasinya. Harapannya dengan indeks literasi yang tinggi di sekitar kawasan hutan, masyarakatnya juga akan jauh lebih mandiri, berdikari, bahagia dan sejahtera.
Perpustakaan BPSILHK Solo juga harus terus bekerja sama dengan pihak lain dan keluar dari zona nyaman untuk lebih mengabdi kepada negeri dan dekat dengan masyarakat. Dan berpedoman bahwa “Membaca menguatkan literasi individu. Literasi individu yang tinggi menguatkan masyarakat dan lingkungan. Masyarakat dan lingkungan yang kuat membuat negara maju, aman dan sejahtera.”
Daftar Pustaka
Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan DAS dan Kepala Desa Somagede. 2021. Surat Perjanjian Kerja sama Nomor 07/SET/PK/KUM.3/11/2021 dan Nomor 140/PKS/2021 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Perpustakaan di Kawasan Sekitar KHDTK Gombong. Surakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan DAS dan Pemerintah desa Somagede.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2017. Panduan Gerakan Literasi Nasional. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diakses dari https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/wp-content/uploads/2017/08/panduan-gln.pdf pada tanggal 26 Maret 2022.
Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
Gambar 5. Kondisi ruangan dan Koleksi perpustakaan KHDTK Gombong
51
TOKOH
SAFEGUARD LINGKUNGAN “KOTA DUNIA UNTUK SEMUA”
Kontributor Liputan: Indah Rahmawati & Tutik Stiyati. Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
WAWANCARA Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas(Dr. Nur Hygiawati Rahayu, ST, MSc)
Isu lingkungan menjadi salah satu perhatian utama dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pembangunan infrastruktur
IKN, diprediksi berpotensi membawa dampak lingkungan, di antaranya mengganggu biodiversitas, kualitas lanskap wilayah, menurunnya stok karbon hutan, ketersediaan air, pencemaran, limbah, kebisingan, sampah, dan sistem drainase. Selain berdampak pada lingkungan, pembangunan IKN juga berpotensi membawa dampak pada kehidupan sosial seperti konflik lahan, akibat perburuan properti lahan dan penggunaan lahan secara ilegal.
Kawasan IKN dikelilingi oleh kawasan ekosistem esensial dan kawasan lindung yang tidak hanya membutuhkan ekstra kehati-hatian (safety regulation) dalam pembangunannya namun juga harus mampu menciptakan simbiosis mutualisme antara ekosistem perkotaan dengan ekosistem hutan hujan tropis. Kawasan ekosistem esensial dan hutan lindung di kawasan IKN perlu dipertahankan, dijaga dan dipulihkan fungsi dan peran ekologisnya. Tak hanya itu, keberpihakan terhadap kelompok rentan dalam hal ini komunitas lokal menjadi bagian penting dalam penyiapan pengamanan dan pengelolaan lingkungan.
Perencanaan IKN disusun berdasarkan rekomendasi dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rapid Assessment yang di susun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019, dan diperdalam pada kajian KLHS Masterplan IKN yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2020.
Untuk mengetahui bagaimana strategi pengendalian lingkungan dan hutan dalam pembangunan IKN sebagai “Kota Dunia untuk Semua” melalui konsep forest city, Tim Redaksi Majalah Standar melakukan wawancara dengan Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber
Daya Air Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Nur Hygiawati Rahayu, ST, MSc,. Petikan wawancara dengan Ibu Yuke, panggilan akrabnya sebagai berikut:
Perencanaan IKN disusun berdasarkan rekomendasi dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Bagaimana KLHS ini mengawal penyusunan masterplan IKN?
Isu lingkungan menjadi perhatian utama dalam penyusunan Rencana Induk IKN. Rencana Induk IKN telah dilengkapi dengan KLHS, di tahap awal untuk menentukan go and no-go area. Selanjutnya KLHS memberikan juga rekomendasi kawasan yang dapat dikembangkan dengan intensitas tinggi dan kawasan yang harus dikonservasi. Sebagai bagian dari penyusunan Rencana Induk IKN, KLHS disusun untuk memastikan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat diintegrasikan dalam Rencana Induk IKN, mengingat kawasan calon IKN memiliki kekayaan sekaligus tantangan ekologis yang tinggi.
52
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
Informasi apa saja yang termuat dalam KLHS sehingga menjadi pedoman bagi penyusunan masterplan IKN?
Penyusunan KLHS menghasilkan berbagai informasi terkait lingkungan hidup yang menjadi pedoman bagi penyusunan Masterplan, khususnya untuk menjaga keseimbangan pembangunan dengan pelestarian lingkungan hidup. Segala hal yang berhubungan dengan aspek lingkungan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN telah dikaji dalam kajian tersebut, yang mana mencakup identifikasi isu lingkungan, analisis, serta alternatif dan rekomendasi untuk memitigasi isu-isu yang telah diidentifikasi dalam kajian tersebut
Visi IKN adalah sebagai “Kota Dunia untuk Semua”. Bagaimana prinsip dan indikator kinerja utama dan target pembangunan IKN sebagai kota dunia berkaitan dengan bidang lingkungan hidup dan kehutanan?
Dalam mendukung kelestarian lingkungan, pembangunan IKN didasarkan pada prinsip mendesain sesuai kondisi alam dan rendah emisi karbon. Terdapat KPI khusus yang mendukung pembangunan IKN sebagai kota dunia untuk semua apabila ditinjau melalui bidang LHK yaitu menargetkan 75% kawasan hijau di wilayah IKN.
Forest city telah menjadi salah satu pembangunan konsep pembangunan IKN. Apa yang melatarbelakangi konsep kota hutan atau forest city dalam pembangunan IKN?
Wilayah IKN memiliki limitasi dan tantangan ekologis yang tinggi. Untuk memastikan visi IKN menjadi kota dunia, pembangunan IKN harus memperhatikan karakteristik wilayah, baik secara ekologi, geologi maupun sosial, sehingga dapat meminimalkan risiko dan dampak dari sisi lingkungan hidup. Sebagian besar wilayah IKN berada di atas kawasan hutan. Luas tutupan lahan berhutan di wilayah IKN saat ini hanya sebesar 42,3%. Kerusakan hutan disebabkan oleh alih fungsi kawasan hutan menjadi peruntukan lain, seperti perkebunan atau pertambangan. Di sisi lain, Wilayah IKN juga memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun fauna. Setidaknya teridentifikasi 140 famili dari 1.967 jenis pohon dan puluhan jenis mamalia, burung dan herpetofauna. Oleh karena itu, pembangunan di kawasan tersebut perlu dibatasi dan memprioritaskan kaidah konservasi.
Bagaimana konsep tersebut dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya di wilayah di mana IKN dibangun?
Forest city didesain dengan tujuan untuk melindungi, mengelola, dan merestorasi hutan di wilayah IKN dalam rangka mengoptimalkan jasa ekosistem hutan dalam pemenuhan daya dukung dan daya tampung, memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pada kawasan IKN dirancang area-area yang mencakup Rimba Nusantara, koridor satwa dalam rangka menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati, ekosistem mangrove, pengelolaan hutan/wanatani berkelanjutan serta Hutan Kota/Ruang Terbuka Hijau (RTH). Untuk mewujudkan pembangunan IKN yang berkelanjutan, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati harus menjadi salah satu aspek yang diprioritaskan. Implikasi konservasi keanekaragaman hayati ditunjukkan dengan penetapan kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi sebagai area yang tidak dibangun (no go area). Selain pemantapan kawasan konservasi dan lindung, beberapa implikasi dalam membangun kawasan tidak terbangun adalah dalam bentuk pembangunan koridor satwa liar.
Pembangunan bagaimanapun pasti akan berdampak pada aspek lingkungan dan sosial. Bagaimana konsep Forest City-IKN dapat mengantisipasi dampak lingkungan yang muncul?
Berdasarkan aspek lingkungan, pembangunan IKN dengan konsep forest city akan mempertimbangkan daya dukung lahan dan keanekaragaman hayati yang ada. Total emisi akibat pembangunan IKN di lahan seluas 56.000 ha diperkirakan mencapai 2,4 juta ton CO2 ekuivalen yang bersumber dari hutan sekunder 29 ribu ton CO2 Equivalen dan hutan tanaman 154 ribu ton CO2 Equivalen. Dengan adanya konsep forest city, diharapkan emisi karbon yang timbul dari pembangunan IKN dapat diminimalkan dan emisi karbon yang dilepaskan dapat tersubstitusi dengan adanya kawasan hijau di IKN. Konsep forest city akan memperbaiki tutupan lahan di sekitar IKN yang selama ini rusak melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Adanya konsep go dan no go area yang diterapkan dalam pembangunan forest city juga akan membantu meminimalkan dampak
53
54
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
negatif yang ditimbulkan dari pembangunan IKN terhadap alam.
Bagaimana dengan antisipasi dampak sosialnya ?
Aspek sosial yang terkait dengan pembangunan forest city salah satunya adalah terkait penguasaan lahan oleh masyarakat di tanah-tanah negara. Terdapat potensi tumpang tindih kejelasan lahan di wilayah IKN mengingat banyaknya penguasaan lahan oleh masyarakat di lahan-lahan negara yang dibebani izin. Keberadaan hal itu akan berdampak pada adanya potensi akuisisi lahan apabila nantinya dibangun infrastruktur di lokasi tersebut. Mengatasi hal tersebut, sebagaimana tertuang dalam KLHS, diusulkan supaya penataan ruang IKN memperhatikan aspek lahan, ekonomi, dan kebudayaan eksisting.
Bagaimana strategi untuk meminalkan dampak sosial?
Dirancang juga kegiatan yang melibatkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dan lokal di wilayah IKN dengan program wanatani berkelanjutan, ekowisata, dan potensi pendapatan dari jasa ekosistem seperti perdagangan karbon hutan; memastikan substansi dan target perlindungan, pengelolaan, dan pemulihan hutan terintegrasi dalam Rencana Induk, Rencana Tata Ruang, Rencana Bangunan dan Lingkungan, serta; melakukan moratorium perizinan usaha dan kegiatan pertambangan, pemanenan kayu, perkebunan di kawasan lindung.
Bagaimana pendekatan terhadap masyarakat adat yang tinggal di wilayah IKN?
Pendekatan pemerintah terhadap masyarakat adat yang saat ini tinggal di calon wilayah IKN dilakukan dengan memastikan proses pembangunan dan IKN yang inklusif, yaitu dengan: 1) Melibatkan lembaga-lembaga masyarakat adat dalam dialog bersama mulai dari perencanaan dan tahap pembangunan selanjutnya untuk menghindari potensi konflik social; 2) Merumuskan protokol mitigasi konflik sosial sebagai acuan seluruh pemangku kepentingan; 3) Menyiapkan posko aduan dan informasi di kecamatan di wilayah IKN untuk memitigasi dan mencegah potensi konflik (kerjasama FORKOPIMDA, aparat kecamatan, desa, tokoh masyarakat, dan Pokja IKN Pusat terkait); 4) Mengembangkan nilai tambah komoditas unggulan masyarakat adat/lokal seperti komoditas biofarmaka dan hasil hutan lainnya; 5) Mengembangkan keahlian wirausaha masyarakat dan fasilitasi usaha di lokasi IKN; 6) Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (a.l. sarana prasarana pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik) di daerah penyangga/sekitar wilayah IKN; serta 7) Menerapkan kebijakan afirmasi untuk turut sertanya masyarakat adat dalam struktur tenaga kerja pembangunan IKN (a.l. kuota dalam pelatihan, pendidikan vokasi)
Standar dan instrumen apa yang akan digunakan untuk meminimalkan dampak lingkungan?
Beberapa kegiatan dirancang untuk meminimalkan dampak dimaksud antara
Gambar 1. Usulan sosial dalam perencanaan spasial yang tertuang dalam KLHS
55
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
lain mempertahankan dan/atau mengurangi deforestasi ekosistem hutan (hutan konservasi, hutan bakau, hutan hujan tropis primer, hutan sekunder) yang menjadi stok karbon dan mempunyai nilai keanekaragaman hayati tinggi; mengelola hutan secara berkelanjutan dan wanatani di area keterlanjuran; merestorasi area terdegradasi (bekas tebangan hutan tanaman, bekas perambahan, dan bekas tambang) dan pengkayaan koridor satwa; membangun hutan dan/atau ruang terbuka hijau (hutan kota, taman kota, taman botani, taman riparian, jalur hijau) di perkotaan sebesar 50 persen dari Kawasan IKN (KIKN).
Seberapa jauh pengaruh benchmarking konsep pembangunan kota berbasis lingkungan dan benchmarking konsep forest city di negara lain dalam konsep Forest City-IKN?
Konsep forest city yang akan diterapkan dalam pembangunan IKN telah melewati proses analisis dan benchmarking dari konsep forest city di negara-negara lain. Contohnya Cleveland, di Ohio Amerika Serikat mendapatkan julukan forest city karena memiliki kepadatan pohon yang tinggi. Kota London di Canada juga mengklaim bahwa kotanya merupakan The Forest City karena membangun permukiman di tengah hutan. Sementara itu di Cina, konsep forest city banyak diadopsi dari berbagai konsep pembangunan kota yang pernah ada seperti sustainable city, eco city, green city dan smart city. Oleh karena itu, dapat juga dikatakan bahwa konsep ini merupakan pengembangan dari berbagai konsep perencanaan kota tersebut yang sangat memperhatikan keberlanjutan kota. Di Cina lebih dari 200 kota di provinsi sudah terlibat dalam rencana pembangunan forest city sejak 2004, dan sebanyak 138 kota telah berstatus forest city dengan rata-rata peningkatan hutannya mencapai 13.333 ha selama periode 2016-2020. Berdasarkan data-data tersebut, diketahui bahwa terdapat beberapa hal yang identik dengan forest city yang kemudian digunakan sebagai dasar penentuan prinsip forest city dalam pembangunan IKN.
Apa saja hal-hal identik tersebut ?
Hal-hal identik di antaranya yaitu julukan untuk kota yang dibangun dari kawasan hutan; kota dengan dominasi vegetasi hutan atau memiliki tutupan pohon yang luas; konsep menghutankan kembali atau konstruksi hutan untuk memperbaiki ekosistem kota dan menciptakan keseimbangan hidup yang berdampingan antara manusia dan spesies lain; kota rimba yang
bentang lanskapnya berstruktur seperti hutan atau memiliki fungsi jasa ekosistem seperti hutan; tersedianya vertical forest, RTH termasuk hutan kota, dan tutupan area hijau di perkotaan yang luas.
Bagaimana konsep forest city dalam pembangunan IKN?
Sebagaimana UU Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN, forest city dalam pembangunan IKN adalah kota yang dibangun dengan menggunakan pendekatan lanskap yang terintegrasi merupakan kota yang didominasi oleh bentang lanskap berstruktur hutan atau RTH yang memiliki fungsi jasa ekosistem, seperti hutan, dan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang berdampingan dengan alam. Prinsip kota hutan adalah kota yang dapat mempertahankan fungsi ekologis hutan dan tujuan pembangunan dalam konsep kota hutan lainnya, seperti penyerapan karbon, konservasi keanekaragaman hayati, dan pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
Secara umum, kota hutan merupakan konsep pembangunan IKN mewujudkan kota berkelanjutan dengan mempertahankan, mengelola, dan merestorasi ekosistem hutan sebagai solusi berbasis alam untuk mengantisipasi berbagai perubahan sosial dan lingkungan seperti dampak perubahan iklim, bencana, kehilangan keanekaragaman hayati, polusi, dan permasalahan kesehatan.
Bagaimana keberadaan hutan di ruang lingkup Forest City IKN ?
Keberadaan hutan di ruang lingkup IKN mencakup antara lain: (a) Hutan sekitar kota: (Wilayah Pengembangan IKN) yang mencakup minimal 75% kawasan hijau antara lain 65% hutan (hutan primer, sekunder, mangrove, agroforestri) dan 10% lainnya tutupan hijau; dan (b) Hutan dalam kota: yakni Hutan sebagai green belt dan koridor keanekaragaman hayati, hutan kota, kebun raya, botanical park, riparian park, jalur hijau, dan ruang terbuka hijau lainnya dengan target minimal 50% KIKN berupa hutan dan/atau ruang terbuka hijau.
Apa tantangan dalam penerapan konsep forest city pembangunan IKN?
Tantangan penerapan konsep forest city dapat dikategorikan secara garis besar dalam empat aspek. Pertama adalah konsep ini dapat dikatakan suatu hal yang baru di Indonesia, sehingga menjadi sorotan dan bisa jadi
hal penciptaan standar dan instrumen untuk mewujudkan forest city, seperti ikut mengawal dan ikut serta dalam perencanaan desain lanskap, pemilihan spesies maupun standar rehabilitasi hutan dan lahan yang tepat untuk pembangunan IKN. Ke depan, hutan di wilayah IKN akan dikelola oleh Badan Otorita, namun diharapkan BSI LHK juga dapat mengawal pengelolaan hutan tersebut sehingga nantinya tercipta hutan yang lestari dan menjadi percontohan pengelolaan hutan di Indonesia.
Nur Hygiawati Rahayu merupakan Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia /Bappenas). Perannya adalah mengkoordinasikan, merumuskan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan, rencana pembangunan nasional, dan strategi di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air. Gelar sarjananya diraih dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan menyelesaikan studi doktoral bidang ekonomi lingkungan dari The University of Queensland, Australia. Ibu Yuke telah berpengalaman lebih dari 20 tahun di Bappenas dan bekerja erat pada isu-isu lingkungan termasuk perubahan iklim, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan, sumber daya air, dan jasa lingkungan hutan.
Ia pernah menjadi anggota delegasi Indonesia pada Climate Talks di Eropa dan Asia, COP 15 UNFCCC Paris, pertemuan UNFCCC di Panama, serta menjadi panelis di berbagai forum dan konferensi internasional, seperti High level politic forum of SDGs dan UNFF di New York, SDGs di Korea Selatan dan banyak lagi. Sebelum posisinya saat ini, Ibu Yuke terlibat dalam berbagai proyek nasional antara lain Rencana Aksi Nasional MDGs, Rencana Nasional Emisi GRK, Strategi Nasional REDD+, analisis lingkungan sumber daya alam negara Indonesia dan proyek-proyek lain yang berkaitan dengan perubahan iklim.
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
adanya ekspektasi tinggi dari publik bagi pemerintah untuk bisa membuktikan bahwa antara keberadaan kota dan eksistensi hutan bisa sejalan. Kedua, adalah mengubah kondisi existing di tingkat tapak menjadi kawasan lindung “Rimba Nusantara” bukanlah hal yang mudah di saat kegiatan non-kehutanan seperti pertambangan, perkebunan, dan pemukiman berada di areal yang akan menjadi fungsi lindung. Ketiga, forest city tidak berhenti pada adanya tutupan hutan 65% tetapi juga tantangan forest city adalah mewujudkan peran sumber daya hutan dalam menjaga ekosistem, mengamankan keanekaragaman hayati (habitat dan koridor satwa), menurunnya tingkat konflik satwa, dan mendukung pembangunan sosial ekonomi berbasiskan jasa ekosistem. Keempat adalah tantangan pada aspek kelembagaan karena IKN dikelola dengan kewenangan khusus yang diharapkan pengelolaan hutan dan lahan terfokus sehingga terwujud integrated land administration.
Bagaimana peran wilayah dan kota yang berdampingan dengan IKN dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan hutan?
Wilayah dan kota satelit sekitar IKN diharapkan dapat ikut menerapkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan mengingat kelestarian suatu wilayah tidak hanya bergantung pada suatu lokasi administratif namun satu kesatuan DAS secara holistik dari hulu ke hilir. Selain itu, dalam perencanaan pembangunan IKN juga telah menerapkan prinsip holistik, integratif, tematik, dan spasial atau yang dikenal dengan istilah HITS.
Perencanaan IKN memperhitungkan keterkaitan dan konektivitas dengan daerah di sekitar wilayah IKN sebagai daerah mitra. Keterkaitan dan konektivitas tersebut tidak hanya dari sisi penyediaan infrastruktur, tapi juga menyangkut hubungan dan kerja sama sosial sosial antar penduduk, keterkaitan ekosistem, serta hubungan dan kerja sama ekonomi yang saling mendukung dan menguatkan. Dengan demikian, pembangunan IKN sebagai kota hutan, kota spons, dan kota cerdas juga harus mengedepankan kemitraan dan kerja sama yang harmonis dengan daerah mitra IKN.
Apa pesan dan harapan untuk kontribusi BSI LHK dalam pengendalian dampak pengembangan kawasan IKN - forest city serta pengelolaan IKN ke depan oleh Badan Otorita?
BSI LHK diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan IKN, khususnya dalam
56
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
POTRET PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN KARHUTLA
Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah dan berhasil
menekan angka karhutla dalam beberapa tahun terakhir secara signifikan. Data siPongi menunjukkan bahwa pada Tahun 2021 terjadi kejadian kebakaran hutan seluas 160.120 ha yang menurun dari tahun 2020 (296.942 ha). Sebanyak hampir 15 persen dari luas karhutla tersebut terjadi di Pulau Kalimantan.
Meskipun karhutla terus dapat diturunkan angkanya, namun upaya pengendalian karhutla khususnya pencegahan (bekerja di depan api) tetap menjadi fokus dan prioritas. Terlebih dengan diluncurkannya Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Pada Surat Keputusan Menteri LHK Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 telah dibentuk Tim Kerja FOLU Net Sink 2030, dimana terdapat satu kelompok kerja khusus di Bidang I yang menangani pengendalian karhutla.
Pada tahun 2021 Balai Penerapan Standar Instrumen LHK Banjarbaru (BPSILHK Banjarbaru) yang saat itu bernama Balai Litbang LHK Banjarbaru, telah melakukan identifikasi dan pemantauan penerapan standar instrumen bidang pengendalian karhutla. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kegiatan ini mencoba memotret pelaksanaan standar instrument dalam pengendalian karhutla pada tingkat tapak. Tim BPSILHK Banjarbaru telah melakukan kajian dan pengambilan data pada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPH, pemegang ijin usaha kehutanan dan perkebunan, serta kelompok masyarakat.
Kebijakan Pengendalian Karhutla
Pengendalian Karhutla telah dilengkapi dengan perangkat kebijakan yang lengkap pada berbagai level. Tim mencatat setidaknya 4 Undang-Undang, 3 Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, 2 Instruksi Presiden, 6 Peraturan Menteri, serta Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dan Eselon I KLHK yang terkait dengan Pengendalian Karhutla. Pemerintah daerah baik Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, maupun Kalimantan Selatan telah mengeluarkan Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur/ Surat Keputusan Gubernur terkait pengendalian karhutla di masing-masing provinsi.Balai Pengendalian Perubahan Iklim (BPPI) Kalimantan juga telah mengeluarkan sejumlah surat keputusan untuk hal-hal yang terkait teknis lapangan. Terdapat juga 4 Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait peralatan-peralatan lapangan pemadaman api yang sebagiannya merupakan produk dari Balai Litbang LHK Banjarbaru.
BPPI wilayah Kalimantan yang berkedudukan di Palangkaraya merupakan UPT KLHK dengan tusi pencegahan karhutla dan sekaligus merupakan koordinator regional DAOPS Manggala Agni Wilayah Kalimantan. Balai Pengendalian Perubahan Iklim (BPPI) Wilayah Kalimantan dilengkapi oleh 13 DAOP Manggala Agni dengan total 52 regu yang tersebar di seluruh Regional Kalimantan. Beberapa pondok kerja dengan 1 regu juga telah dibangun pada areal-areal yang memiliki kerawanan tinggi. Inovasi “Halo-Halo Karhutla” telah diluncurkan oleh BPPI Kalimantan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan
CERITA TAPAK
Sujarwo SujatmokoBalai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banjarbaru, E-mail: [email protected]
Pengendalian kebakaran bersama masyarakat merupakan cara efektif untuk pencegahan dan penanganan karhutla. Jika diperlukan, dapat dilakukan perhitungan kebutuhan regu berdasarkan luasan areal yang dapat ditangani. Masyarakat Peduli Api (MPA) yang telah dilatih keterampilan dalam pengendalian karhutla telah diperlengkapi dengan peralatan tangan dan mesin pemadaman karhutla serta peralatan komunikasi. Peralatan pengendalian karhutla yang telah tersedia adalah: kendaraan slip on tank (water tank), pompa punggung (jet shooter), peralatan tangan (kepyok, sekop api, cangkul api, garu api) serta personal use.
57
akan bahaya dan dampak karhutla melalui upaya pencegahan. Dalam pengedalian karhutla, BPPI berkoordinasi berbagai stakeholder terkait di derah.
Pada tingkat KPH, semua KPH di ketiga provinsi telah membentuk Brigade Pengendalian Karhutla (Dalkarhutla) yang pembentukannya diatur oleh Peraturan Gubernur pada masing-masing provinsi. Dinas kehutanan pada masing-masing provinsi bertindak sebagai koordinator dari Brigade Dalharhutla. Sebagai contoh, Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Tanah Laut di Provinsi Kalimantan Selatan telah dilengkapi dengan Brigade Dalkarhutla. KPH tanah Laut juga telah membentuk 19 kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang telah dilatih keterampilan dalam pengendalian karhutla. Regu MPA juga telah diperlengkapi dengan peralatan tangan dan mesin pemadaman karhutla serta peralatan komunikasi. Peralatan pengendalian karhutla di KPH Tanah laut yang telah tersedia adalah: kendaraan slip on tank (water tank), pompa punggung (jet shooter), peralatan tangan (kepyok, sekop api, cangkul api, garu api) serta personal use. Inovasi modifikasi kendaraan pengangkut air juga telah dikembangkan bersama MPA untuk menjangkau daerah yang memiliki akses sulit dengan memodifikasi kendaraan roda 3 yang dilengkapi tangki air dan mesin pemadam portable.
Penerapan Standar Instrumen Karhutla
Tim telah melakukan pengambilan data pada pemegang ijin berusaha kehutanan dan perkebunan. Untuk pemegang ijin kehutanan, tim mengambil sampel IUPHHK RE dengan konsesi areal gambut dan dan IUPHHK HTI pada lahan mineral. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa kedua pemegang ijin telah berupaya memenuhi P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Keduanya telah memiliki organisasi brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta melaksanakan pelatihan sumberdaya manusia pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sarana dan prasarana pengendalian karhutla pada kedua pemegang ijin telah lengkap memenuhi standar yang disyaratkan, seperti: menara pemantau api, sarana komunikasi, sarana transportasi dan pengangkutan, pos patroli, tanki dan peralatan pemadaman.
Kedua pemegang ijin juga secara operasional telah memiliki dan menjalankan SOP Penyelenggaran Karhutla. Inovasi juga telah dilaksanakan pada kedua perusahaan, seperti pembangunan Sistem Pengendalian Dini Gambar 1 Menara pemantau api
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
58
STANDAR: Better Standard Better Living − Vol. 1 No.2, Maret 2022
(Early Warning System/EWS) berbasis teknologi informasi, pemanfaatan drone pemantau. Perusahaan telah menetapkan pengendalian karhutla sebagai Key Performance Indicator dalam kinerja perusahaan. Pada IUPHHK-HTI yang menjadi obyek pengambilan data di Provinsi Kalimantan Selatan telah mendapatkan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan dalam pengendalian karhutla.
Pada pemantauan di pemegang Hak Guna Usaha/ HGU perkebunan, tim BPSILHK Banjarbaru juga telah melihat adanya upaya pemenuhan standar pengendalian karhutla. Perusahaan telah membentuk Tim Dalkarhutla yang telah mendapatkan pelatihan, membuat sekat-sekat bakar dan kantong air. Perusahaan juga telah menyediakan peralatan yang memadai sesuai Permentan 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 yang juga mengatur tentang sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan seperti: mesin induk pemadam, mesin pemadam portable, peralatan tangan, personal use dan mobil tangki pemadam. Untuk kegiatan pemantauan karhutla di areal kerja perusahaan juga dilengkapi menara pantau api yang memiliki tinggi 25 m. Pengurangan potensi bahan bakar dilakukan dengan pengembangan bidang usaha peternakan sapi yang digembalakan di areal kebun. Pembinaan terhadap MPA yang telah dibentuk pemerintah juga rutin dilakukan, antara lain pelatihan penanggulangan karhutla dan turut membantu
peralatan tangan bagi regu MPA.
Terlepas dari masih sangat minimnya sampel pemantauan, tim BPSILHK Banjarbaru mencatat beberapa hal penting di lapangan terkait dengan penerapan standar instrumen dalam pengendalian karhutla. Penilaian kepatuhan pemegang ijin usaha dapat segera dilakukan secara menyeluruh seiring dengan terbitnya SK Dirjen PPI nomor P.2/PPI/SET.8/KUM.1/2/2021 tentang Pedoman Uji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Pemegang izin Usaha Pemanfaatan Hasik Hutan Kayu pada Hutan Alam/ Tanaman/ Restorasi Ekosistem, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau Perkebunan dalam Pengendalian Kebakaran Hutan. Selain itu, sarana menara pemantau api untuk pemegang ijin memerlukan memerlukan evaluasi standar spesifikasi dan letak yang mampu menjangkau luas areal pengamatan secara optimal. Penguatan DAOPS, Brigade, Regu dan MPA perlu terus dilakukan mengingat pengendalian kebakaran bersama masyarakat merupakan cara efektif untuk pencegahan dan penanganan karhutla. Jika diperlukan, dapat dilakukan perhitungan kebutuhan regu berdasarkan luasan areal yang dapat ditangani. Terlepas dari topik standar, berbagai inovasi pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan bahan organik untuk mengurangi resiko kebakaran seperti cuka kayu, kompos blok dan pelet pakan ternak dapat pula terus dikembangkan.
Gambar 2. Peralatan pengendalian karhutla
59