H a k HAKIM, MAHKUM FIH DAN MAHKUM 'ALAIH
Transcript of H a k HAKIM, MAHKUM FIH DAN MAHKUM 'ALAIH
1 | H a k i m , M a h k u m F i h d a n M a h k u m „ A l a i h
Kelompok 7 (Fiqh dan Ushul Fiqh):
1. Aris Munandar (NIM. 12810030)
2. Hikmah Suprihatin (NIM. 12810021)
3. Laela Mu‟arifah (NIM. 12810013)
HAKIM, MAHKUM FIH DAN MAHKUM ‘ALAIH
A. HAKIM
1. Pengertian
Secara etimologi hakim memiliki dua pengertian. Pertama, hakim artinya
pembuat, penetap, sumber hukum yaitu Allah SWT., kedua hakim berarti penemu,
penjelas, pengenal, penyingkap hukum, dalam pengertian ini termasuk di
dalamnya para mujtahid. Sumber hukum yang hakiki adalah Allah SWT. dasarnya
adalah surat Al – An‟am ayat 57.
Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran)
dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang
kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah
hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang
paling baik".
Allah adalah hakim, baik perbuatan itu sudah dijelaskan Allah secara
langsung atau Allah memberi petunjuk langsung kepada para mujtahid. Syariah
secara onotlogis dapat berupa hukum agama dan hukum positif. Syari‟ah adalah
2 | H a k i m , M a h k u m F i h d a n M a h k u m „ A l a i h
hukum agama, karena merupakan realitas metafisik dari ketentuan – ketentuan
dalam al – Qur‟an dan Hadis. Artinya secara idealitas syari‟ah adalah hukum yang
dibuat atau ditentukan oleh Syari‟ yang mutlak, yaitu Allah SWT. Syari‟ah adalah
kehendak Illahi sehingga bersifat teologis. Di sisi lain syari‟ah adalah hukum
positif, karena merupakan perkembangan dari „amal (praktek masyarakat) dan
yurisprudensi (hasil keputusan para hakim/qadhi). Ini adalah wujud realitas
syari‟ah yang dijalankan oleh umat Islam.
Secara epistemologis, ketentuan dalam hukum positif Islam ini berasal dari
hasil ijtihad para mufti atau mujtahid, yang menurut Syatibi, juga merupakan
Syari‟ (bukan mutlak), karena mereka menjalankan fungsi atas nama Tuhan,
bukan dalam hak mereka sendiri.
2. Kedudukan Mujtahid dalam Penetapan Hukum Islam
Tugas ijtihad pertama kali diberikan khusus kepada nabi Muhammad saw,
yang merupakan penafsir pertama dan utama al – Qur‟an. Setiap turun wahyu,
Nabi menjelaskan maksud dan kandungan wahyu tersebut kepada sahabat –
sahabatnya. Pada masa selanjutnya penjelasan Nabi ini dijadikan sebagai second
source hukumm Islam dan disebut dengan Sunnah atau Hadis.
Tugas dan kewenangan ijtihad ini dilanjutkan oleh generasi pasca Nabi
hingga sekarang. Rumas hukum para ulama menjadi hukum Islam in action, yang
secara teoritis berdasarkan pada ketentuan al – Qur‟an dan Hadis.
3. Metode Istimbat Hukum Syara’
Mengetahui hukum – hukum Allah (hukum perbuatan mukallaf) adalah
dengan menggunakan dalil – dalil dan isyarat yang disyariatkan untuk istimbat
hukum. Dari sinila para ulama menyusun pola penalaran, baik berupa kaidah –
kaidah penafsiran maupun metode istimbat hukum.
Secara umum pola penalaran itu dibagi menjadi tiga:
a. Penalaran bayany adalah metode penalaran (penafsiran) yang bertumpu
pada arti kata (dialat) dan kaidah – kaidah kebahasaan.
3 | H a k i m , M a h k u m F i h d a n M a h k u m „ A l a i h
b. Penalaran ta‟lily adalah pola penafsiran yang dilakukan dengan cara
menemukan „illat (alasan penetapan hukum, kausa efektif, ratio
legis/tambatan hukum) yang terkandung dalam nash.
c. Penalaran istislahy adalah pola penalaran yang bertumpu pada
kemaslahatan yang terkandung dalam nash.
4. Kedudukan Akal terhadap Wahyu
Para ulam terbagi kedalam 2 kelompok, yaitu Mu‟tazilah di satu sisi
dengan Asy‟ariyah dan Maturidiyah di sisi yang lain. Kelompok Mu‟tazilah
mengaggap bahwa akal dapat menjadi sumber hukum yang ketiga, dan kedudukan
wahyu adalah konfirmasi bagi akal. Bagi kelompok Asy‟ariyah dan Maturidiyah
akal dapat berdiri sendiri sebagai sumber hukum, kedudukan wahyu adalah
sebagai sumber informasi.
Ulama yang beraliran Mu‟tazilah misalnya, cenderung mendahulukan akal
daripada wahyu, sedangkan ulama aliran Asy‟ariyah lebih mendahulukan wahyu
daripada akal. Dalam pandangan ulama Asy‟ariyah, jika dalil naqli bertentangan
dengan pemahaman akal, maka akal yang harus ditundukan. Akal tidak dapat
menetapkan kemaslahatan. Hal ini berbeda dengan pandangan Mu‟tazilah, bahwa
akal dapat mengetahui manfaat dan mafsadat serta mampu menetapkannya.
Asy – Syatibi berupaya menengahi dua pendapat ini dengan menyatakan
bahwa manusia dengan akalnya dapat mengetahui kemaslahatan, namun
wahyulah yang menetapkan dan membenarkannya.
4 | H a k i m , M a h k u m F i h d a n M a h k u m „ A l a i h
B. MAHKUM FIH
1. Pengertian dan Syarat mahkum fih.
Secara Etimologi mahkum fih adalah obyek hukum, artinya suatu
perbuatan mukalaf yang berhubungan dengan hukum syari‟. Sedangkan secara
istilah, mahkum fih adalah baik itu perbuatan atau pekerjaan seorang mukalaf
yang dapat dinilai hukumnya. Jadi, mahkum fih adalah perbuatan mukalaf yang
menjadi objek dari hukum syara‟.
Setiap hukum dari syari‟ harus berhubungan dengan perbuatan mukallaf
baik itu sebuah tuntutan, pilihan, atau penetapan. Namun, menurut fuqaha, tidak
semua perbuatan hukum dapat disebut sebagai mahkum fih. Jadi, untuk
mengetahui perbuatan mukallaf tersebut mahkum fih atau tidak, para fuqaha
menetapkan beberapa syarat. Syarat mahkum fih adalah :
a. Perbuatan itu harus diketahui oleh mukallaf secara sempurna. Sempurna
yang dimaksudkan yaitu mengetahui tentang rukun, syarat, dan
sebagainya. Berdasarkan hal ini, nash nash yang mujmal tidak sah
mentaklifikannya pada mukallaf , kecuali jika telah dijelaskan rasulullah
kita dapat melanjutkannya.
b. Diketahui bahwa tuntutan itu datang dari otoritas yang berwenang dalam
hukum dan dari orang yang wajib diikuti pentaklifannya. Yang dimaksud
pengetahuan mukallaf terhadap yang ditaklifinnya adalah kemungkinan
untuk mengetahuinnya, bukan pengetahuan secara langsung.
c. Perbuatan itu memungkinkan dikerjakan /ditinggalkan, konsekuensinya:
1. Tidak boleh ada taklif yang mustahil. Baik itu mustahil secara
substansinya atau mustahil karena sesuatu lainnya (menurut adat).
Mustahil secara substansi adalah sesuatu yang tidak masuk akal,
yaitu sesuatu yang tidak bisa terbayangkan oleh akal tentang
kebaradaannya. Misalnya, pewajiban dan pengharaman dalam satu
waktu, satu tempat, dan satu masalah. Sedangkan mustahil karena
sesuatu lainnya (menurut adat) adalah sesuatu yang terbayangkan
5 | H a k i m , M a h k u m F i h d a n M a h k u m „ A l a i h
oleh akal namun tidak diterima oleh adat dan hukum alam.
Misalnya, adanya tanaman tanpa ada bibitnya.
2. Tidak sah melaksanakan perbuatan atas nama orang lain karena itu
bukan taklif untuknya, sehingga tidak ada pertanggungjawaban
terhadap perbuatannya. Segala sesuatu yang ditaklifkan pada
manusia yang dikhususkan pada orang lain adalah nasehat, amar
m‟ru dan melarang yang munkar
2. Kriteria Taklif
Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang terkena taklif dalam
hukum syara‟. Dalam hal ini ada dua pendapat yang berbeda, yaitu
a. Kelompok Asy‟ariyah, Maturidyah, dan sebagian Hanafiyah, berpendapat
bahwa yang terkena taklifinnya itu semua manusia, termasuk orang kafir.
Karena ayat taklif bersifat umum, dan ada siksa terhadap orang yang tidak
melakukan hukum syara‟.
b. Mayoritas Hanafiyan dan Abu Hamid-Asyfarayni berpendapat bahwa
taklif hanya berlaku untuk orang islam. Orang kafir tidak terkena taklif
karena jika orang kafir dikenakan taklif maka akan terjadi pelegalan
terhadap kekafiran, dan jika orang kafir masuk islam, maka orang kafir
tersebut harus mengqadha semua taklif yang mereka tinggalkan selama
mereka kafir.
3. Macam – macam Mahkum Fih
a. Jika ditinjau dari keberadaan materialnya dan syara‟ Mahkum Fih dibagi
menjadi tiga, yaitu:
Perbuatan material yang tidak termasuk perbuatan dengan syara‟.
Misalnya, makan minum dan lain lain.
Perbuatan secara material dan menjadi hukum syara‟. Misalnya
pencuri, perzinaan dan lain lain.
6 | H a k i m , M a h k u m F i h d a n M a h k u m „ A l a i h
Perbuatan secara material ada dan diakui syara‟ serta
mengakibatkan hukum syara‟ yang lainnya. Misalnya, pernikahan,
jual beli, dan lain lain.
b. Jika dilihat dari hak yang terdapat didalam perbuatan itu, terdapat 4 jenis
Mahkum Fih, yaitu:
Semata mata hak allah, yaitu segala sesuatu yang menyangkut pada
kemaslahatan umum.
Semata mata hak hamba, yaitu yang menyangkut hak pribadi
seseorang, seperti ganti rugi barang yang rusak. Seperti hukuman
qazaf.
Kompromi antara hak Allah dan hak Hamba, tetapi hukum Allah
lebih menonjol.
Kompromi antara hak Allah dan hak Hamba, seperti hukuman
qisas.
B. MAHKUM ‘ALAIH (MUKALLAF)
Yang dimaksud dengan mahkum alaih, orang mukallaf yang perbuatannya
berhubungan dengan hukum syar‟i. atau dengan kata lain, mahkum alaih adalah
orang mukallaf yang perbuatannya menjadi tempat berlakunya hukum allah.
Menurut ulama‟ ushul fiqh telah sepakat bahwa mahkum Alaih adalah seseorang
yang perbuatannya dikenai kitab Allah, yang disebut mukallaf. Sedangkan
keterangan lain menyebutkan bahwa Mahkum Alaih ialah orang-orang yang
dituntut oleh Allah untuk berbuat, dan segala tingkah lakunya telah
diperhitungkan berdasakan tuntutan Allah itu (Sutrisno, 1999). Jadi, secara singkat
dapat disimpulkan bahwa Mahkum Alaih adalah orang mukallaf yang
perbuatannya menjadinya tempat berlakunya hukum Allah.
Dinamakannya mukalaf sebagai mahkum alaih adalah karena dialah yang
dikenai (dibebani) hukum syara‟. Ringkasnya yang dinamakan mahkum
alaih adalah orang atau mukallaf itu sendiri.
7 | H a k i m , M a h k u m F i h d a n M a h k u m „ A l a i h
Syarat-Syarat Mahkum ‘Alaih
Ada dua persaratan yang harus dipatuhi agar seorang, mukallaf sah ditaklifi.
a. Orang tersebut memahami dalil-dalil taklifi (pembebanan) itu dengan
sendirinya, atau dengan perantaraan orang lain. Orang yang tidak mampu
memahami dalil-dalil itu tidak mungkin mematuhi apa yang ditaklifkan
kepadanya. Kemampuan memahami dalil-dalil taklif hanya dapat terwujud
dengan akal, karena akal adalah alat untuk mengetahui apa yang ditaklifkan itu.
Oleh karena akal adalah hal yang tersembunyi dan sulit diukur, maka
menyangkutkan taklif itu ke hal-hal yang menjadi tempat anggapan adanya akal,
yaitu baligh. Barang siapa yang tidak baligh dan tidak keliatan cacat akalnya
berarti ia telah cukup kemampuan untuk ditaklifi.
Berdasarkan hal di atas anak-anak atau orang gila tidak dikenai taklif
tersebut. Begitu juga dengan orang yang lupa, tidur, dan mabuk. Sebab dalam
keadaan demikian mereka tidak dapat memahami apa-apa yang ditaklifkan kepada
mereka.
Hal ini senada dengan sabda Rasulullah Saw:
حت يحت و ه مجىىن حت : ل ه ب ه ىائ حت يستيلظ و ه ص
ي ي
“Diangkatlah pembebanan hukum dari tiga (jenis orang): orang tidur sampai ia
bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh.” (H.R. al-
Bukhari, Abu Daud, al-Tirmidzi, Ibn Majah dan al-Daruquthni dari Aisyah dan Ali
bin abi thalib).
Begitu juga dalam Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat: 43 sebagai berikut
ة وأوت سكا ي حت تع مى ما تلى ىن ول يا أيها ذيه آمىى ل تلربى ص
جىبا إل ابر سبيل حت تغتس ى وإن كىت مرض أو س ر أو جاء أحد
مى صعيد طيبا امسحى مىك مه غائط أو لمست ىساء تجدو ماء تيم
كان ى غ ى (43)بىجىهك وأيديك إن لل
8 | H a k i m , M a h k u m F i h d a n M a h k u m „ A l a i h
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam
Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula
hampiri masjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu
saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau
datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian
kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik
(suci) sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi
Maha Pengampun.”(QS. An-Nisa ayat: 43).
Dan bagi orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab dan orang yang
tidak bisa memahami dalil-dalil syara‟ baik dari al-Qur‟an maupun dari as-
Sunnah, seperti bangsa-bangsa selain bangsa Arab, maka tidak sah menuntut
mereka secara syara‟ kecuali mereka belajar bahasa Arab ataupun mereka bisa
memahami nash-nasnya, atau jika dalil-dalil tersebut diterjemahkan ke dalam
bahasa mereka.
b. Orang tersebut “ahli”, disini berarti layak dan pantas. Contohnya seperti
seseorang dikatakan ahli untuk mengurus wakaf berarti ia pantas untuk diserahi
tanggung jawab mengurus harta wakaf.
1. Keadaan manusia dihubungkan dengan keahlian wajib
Hubungan manusia dengan ahliayah al-wujub ( kewajiban menerima hak dan
kewajiban) yang ada padanya. Diliat dari segi ini manusia terbgai menjadi dua:
a. Mempunyai ahliyah Al-wujud yang tidak penuh atau tidak sempurna,
yaitu apabila pantas diberikan kepadanya hak-hak, tetapi tidak
pantasdipikulkan kepadanya kewajiban-kewajiban atau
sebaliknya. Misalnya, janian( embrio) dalam perut ibunya ia
mempunyai hak untuk menerima warisan atau wasiat, tetapi tidak
mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Sebaliknya, orang mati
yang masih mempunyai hutang, hak orang yang berpiutang mmasih ada
diatasnya. sehingga ia –melalui ahli warissnya- punya kewajiban untuk
membayar utangnya, tetapi ia tidak mempunyai hak apa-apa lagi.
9 | H a k i m , M a h k u m F i h d a n M a h k u m „ A l a i h
Mempunyai ahliah al-wujud yang penuh, yaitu pantas diberikan
kepada hak-hak dan pantas diberikan kkepadanya kewajiban-kewajiban
ini adalah keahlian (ahliah) yang dimil;iki seseorang semenjak ia lahir
dan tetap dimilikinya selama ia masih hidup, meskipun ia kehialangan
akal atau gila. Yang dimaksud disisni adalah kewajiban-kewajiban yang
berkaitan dengan harta benda, seperti kewajiban zakat bila yang dikenai
kewajiban itu belum sempurna akalnya, walinya lah yang mewakilinya
menunaikan kewajiban tersebut.
b. Keahlian wajib yang sempurna, jika mukallaf layak menerima hak dan
melaksanakan kewajiban. Hal ini dimiliki oleh setiap orang sejak
dilahirkan. Yakni sejak usia kanak-kanak, usia mumayyiz, sampai
sesudah baligh dalam keadaan dan kondisi lingkungan yang
bagaimanapun ia telah memiliki keahlian wajib sempurna.
2. Keadaan manusia dihubungkan dengan keahlian melaksanakan.
Hubungan manusia dengan ahliyyah al-ada‟ (kemmampuan berbuat) yang
ada padanya. Diliat dari segi ini manusia dibagi menjadi tiga bagian.
a. Tidak punya atau hilang ahliyyahnya sama sekali. Misalnya, anak-anak
pada massa anaknya dan orang gila pada masa gilanya,karena mereka tidak
mempunyai akal. Oleh sebab itu perbuatan dan ucapannyatidak mempunyai
konsekwensi hokum dan semua akad atau perikatan ayang dilakukannyaitdak sah
atau tidak batal. Bila mereka melakukan suatu tindakna pidana atas jiwa dan
hartanya, yang dikenakan padanya hanya hukum denda, yaitu diyat yang
dibunuhnyadan mengganti harta yang rusak atau diambilnya, bukan hukum badan,
bukan juga hukum kisas.
b. Mempunyai ahliyah al-ada yang tidak sempurna, misalnya mumaiiyaz dan
orang yang kurang akal. Akal mereka tidak cact dan juga tidak hila.
10 | H a k i m , M a h k u m F i h d a n M a h k u m „ A l a i h
c. Mempunyai ahliyyah yang penuh , yaitu orang dewasa dan sehat akalnya.
Maka ahliyat yang sempurna dapat trealisasikan dengan kedewasaan dan
berakal.[2]
Penghalang Keahlian
Para ulama‟ushul fiqh sepakat menyatakatan bahwa penentuan cakap atau
tidaknya seseorang dalam bertindak hukum dilihat dari segi akalnya. Akan tetapi
mereka sepakat, bahwa sesuai dengan hukum biologis, akal seseorang bisa
berubah, kurang dan hilang sama sekali, sehingga mengakibatkan mereka
dianggap tidak cakap lagi dalam bertindak hukum, baik dalam tindakan hukum
yang berkaitan dengan masalah tertentu maupun dalam bidang-bidang yang
terbatas. Dalam hubungan ini, ulama‟ushul fiqh menyatakan bahwa kecakapan
bertindak hukum seseorang bisa berubah yang disebabkan:
1). „awaridh al-samawiyyah ( عى ض سما و ), maksudnya halangan yang
datangnya dari Allah, bukan disebabkan perbuatan manusia, seperti gila, dungu,
perbudakan, mard maut (sakit yang berlanjut dengan kematian) dan lupa.
2). „Awaridh al-muktasabah ( عى ض مكتسبت ), maksudnya halangan yang
disebabkan perbuatan manusia, seperti mabuk, bodoh dan hutang.
Kedua bentuk halangan yang menyebabkan berubahnya kecakapan
bertindak hukum seseorang itu sangat berpengaruh terhadap tindakan hukumnya.
Menurut ulama‟ushul fiqh, perubahan kecakapan bertindak hukum itu adakalanya
bersifat menghilangkan sama sekali, mengurangi atau mengubahnya.
Referensi:
Khallaf, Abdul Wahhab. 2003. Ilmu Ushul Fikih, Kaidah Hukum Islam. Jakarta:
Pustaka Amani.
Khallaf , Abdul Wahab. 1994. Ilmu Ushul Fiqh. Semarang: Dina Utama.
Sodiqin , Ali. 2012. Fiqh dan Ushul Fiqh. Yogyakarta: Beranda Publishing.










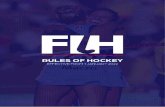
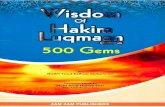

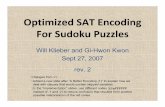













![FYdgYdcYf]k Yf\ FYdgYj]f]k - Samagra](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631f358f13819e2fbb0fa1db/fydgydcyfk-yf-fydgyjfk-samagra.jpg)



