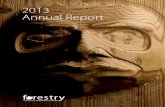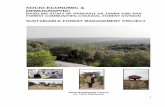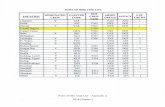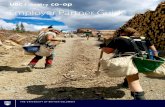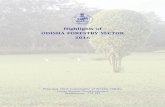Forestry Socio and Economic Research Journal - Portal ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Forestry Socio and Economic Research Journal - Portal ...
Forestry Socio and Economic Research Journal
Volume 13 Nomor 3, Desember Tahun 2016
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANMinistry of Environment and Forestry
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASIForestry Research, Development and Innovation Agency
Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change
BOGOR - INDONESIA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL, EKONOMI, KEBIJAKAN DAN PERUBAHAN IKLIM
ISSN: 1979-6013eISSN: 2502-4221
TERAKREDITASINo. 687/AU3/P2MI-LIPI/07/2015
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) No. 818/E/2015 Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan memuat karya tulis ilmiah dari hasil-hasil penelitian bidang sosial, ekonomi dan .lingkungan kehutanan yang meliputi aspek: sosial ekonomi kemasyarakatan, sosiologi kehutanan, politik dan ekonomi kehutanan, studi kemasyarakatan, kebijakan lingkungan, ekonomi kehutanan/sumber daya hutan, ekonomi sumber daya alam, ekonomi pertanian, ekonomi ekoturisme, furniture value chain, kehutanan masyarakat, kebijakan kehutanan, kebijakan publik, perubahan iklim, ekologi dan manajemen lanskap, konservasi sumber daya alam, kebakaran hutan dan lahan, , konservasi tanah dan air, agroklimatologi dan lingkungan, mitigasi REDD+, adaptasi global climate changeperubahan iklim. Terbit pertama kali tahun 2001, terakreditasi tahun 2006 dengan nomor 60/Akred-LIPI/P2MBI/12/2006. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan terbit dengan frekuensi tiga kali setahun (April, Agustus, Desember).
Forestry Journal Socio and Economic Research is an accredited journal, based on the decree of Director of Indonesian Science Institute (LIPI) No . . 818/E/2015 This journal publishes result research in forest socio-economics and environment which cover: socio economics on community, sociology forestry, political dan economic on forestry, social studies, environmental policy, forest resource economics, natural reources economics, agricultural economy, ecotourism ekonomy, furniture value chain, community forestry, forestry policy, public policy, climate change, ecology and landscpae management, conservation of natural resources, land and forest fire, global climate change, soil and water conservation, agro-climatology and environment, mitigation REDD+, adaptation to climate change. First published in 2001, accredited by LIPI in 2006 with number 60/Akred-LIPI/P2MBI/12/2006. The Journal published three times annually (April, August, and December).
PENANGGUNG JAWAB/PELINDUNG : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
DEWAN REDAKSI (EDITORIAL BOARD) :
Ketua (Editorial in Chief) : Dr. Ir. Hariyatno Dwiprabowo, M.Sc. (Ekonomi Kehutanan, Badan Litbang dan Inovasi)
Editor Bagian (Section Editor) : 1. M. Zahrul Muttaqin,S.Hut,M.For.Sc. (Ekonomi Kehutanan, P3SEKPI) 2. R. Deden Djaenudin,S.Si,M.Si. (Ekonomi Kehutanan, P3SEKPI)
Mitra Bestari (Peer Reviewers) : 1. Prof. Dr. Ir. Herry Purnomo, M.Comp. (Kebijakan Kehutanan, Mitigasi, REDD+, Adaptasi Perubahan Iklim dan Furniture Value Chain, CIFOR)
2. Prof. Dr. Dudung Darusman, M.Sc. (Kebijakan Kehutanan, Institut Pertanian Bogor) 3. Dr. Ir. Boen M. Purnama (Ekonomi dan Sumberdaya Hutan, IPDN) 4. Prof. Dr. Ir. Hadi Susilo Arifin, M.Sc. (Ekonomi dan Manajemen Lanskap, IPB) 5. Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. (Kebakaran Hutan dan Lahan, Perusakan Lingkungan
Hidup dan Global Climate Change, IPB) 6. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Sosial Ekonomi Kemasyarakatan, Kebijakan Publik, Perubahan
Iklim dan Konservasi Sumber Daya Alam, P3SEKPI) 7. Dr. Ir. Dodik R. Nurrochmat, M.Sc. (Politik dan Ekonomi Kehutanan, IPB) 8. Dr. Ir. A. Ngaloken Gintings, MS. (Konservasi Tanah dan Air, MKTI) 9. Dr. I Wayan Susi Dharmawan, S.Hut., M.Si. (Hidrologi dan Kesuburan Tanah, Pusat Litbang Hutan)
Anggota (Reviewer) : 1. Dr. Fitri Nurfatriani, S.Hut, M.Si. (Ekonomi Kehutanan, P3SEKPI) 2. Dr. Ir. Retno Maryani, M.Sc. (Ekonomi Kehutanan, P3SEKPI) 3. Dr. Mety Ekayani, S.Hut., M.Sc. (Resources Economics, Ecotourism Economics, Environmental Policy,
UGM) 4. Prof. Dr. Ir. Irsal. Las, MS. (Agroklimatologi dan Lingkungan, Balai Besar Litbang Sumberdaya
Pertanian) 5. Drs. Lukas R. Wibowo, M.Sc., Ph.D. (Sosiologi Kehutanan, P3SEKPI) 6. Prof. Dr. Ir. Didik Suharjito, MS. (Sosiologi Kehutanan dan Kehutanan Masyarakat, IPB) 7. Dr. Ir. Satria Astana, M.Sc. (Ekonomi Kehutanan, P3SEKPI) 8. Prof. Herman Hidayat (Studi dan Kemasyarakatan, LIPI) 9. Dr. Ir. Erwidodo, MS. (Ekonomi Pertanian, Puslitsosek Pertanian) 10. Dr. Edi Basuno (Ekonomi Pertanian, CIVAS) 11. Dr. Ir. Triyono Puspitojati, M.Sc. (Ekonomi Kehutanan, P3SEKPI) 12. Dra. Setiasih Irawanti, M.Si. (Ekonomi Kehutanan, P3SEKPI) 13. Ir. Subarudi, M. Wood.Sc. (Sosiologi Kehutanan, P3SEKPI)
REDAKSI PELAKSANA (EDITORIAL TEAM) :Penyunting Bahasa (Copy Editor) : 1. Mohamad Iqbal, S.Hut., M.Si. 2. Dra. Wahyuning Hanurawati 3. Drh. Faustina Ida Harjanti, M.Sc.
Penyunting Format (Layout Editor) : Bintoro, S.Kom.Proof Reader : Gatot Ristanto, S.H., MM.Sekretariat (Secretariat) : 1. Ratna Widyaningsih, S.Kom. 2. Fulki Hendrawan, S.Hut. 3. Parulian Pangaribuan
Diterbitkan oleh (Published by):Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim (Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change)Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi (Forestry Research, Development and Innovation Agency)Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ministry of Environment and Forestry)Alamat ( ) : Jl. Gunung Batu No. 5 Po Box 272 Bogor 16118, IndonesiaAddressTelepon ( ) : 62-251-8633944PhoneFax. ( .) : 62-251-8634924FaxE-mail : [email protected]; [email protected] ( ) : www.puspijak.orgWeb
Volume 13 Nomor 3, Desember Tahun 2016
ISSN: 1979-6013eISSN: 2502-4221
ISSN: 1979-6013eISSN: 2502-4221
TERAKREDITASINo. 687/AU3/P2MI-LIPI/07/2015
Forestry Socio and Economic Research Journal
Volume 13 Nomor 3, Desember Tahun 2016
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANMinistry of Environment and Forestry
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASIForestry Research, Development and Innovation Agency
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL, EKONOMI, KEBIJAKAN DAN PERUBAHAN IKLIM
Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change
BOGOR - INDONESIA
Ucapan Terima Kasih
Dewan Redaksi Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mitra bestari (peer reviewers) yang telah menelaah naskah yang dimuat pada edisi Vol. 13 No. 3 Desember tahun 2016 :
1. Dr. I Wayan S Dharmawan, S.Hut., M.Sc2. Dr. Ir. Boen M Purnama, M.Sc3. Prof. Ris. Djaban Tinambunan, MS4. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc
DAFTAR ISI
145 - 154
155 - 163
165 - 176
177 - 187
189 - 199
ISSN: 1979-6013eISSN: 2502-4221
TERAKREDITASINo. 687/AU3/P2MI-LIPI/07/2015
Forestry Socio and Economic Research Journal
Volume 13 Nomor 3, Desember Tahun 2016
DAUR OPTIMAL TEGAKAN GMELINA PADA DUA PROYEK KARBON: MEMPERPANJANG DAUR DAN AFORESTASI (The Optimal Rotations of Gmelina Stand on Two Carbon Projects: engthening Rotation and Afforestation)LYonky Indrajaya & Satria Astana .................................................................................................
HARGA OPTIMAL TIKET MASUK WISATA ALAM BANTIMURUNG, SULAWESI SELATAN (Optimal Price of Admission Bantimurung Natural Park, South Sulawesi)Wahyudi Isnan ...............................................................................................................................
SINERGI TATA RUANG TERHADAP PELAKSANAAN REDD+: STUDI KASUS DI KABUPATEN KATINGAN, KALIMANTAN TENGAH (Synergy of Spatial Planning for REDD+ Implementation at Katingan District, Central Kalimantan)Nugroho Adi Utomo & Santun R. P. Sitorus .............................................................................
ORIENTASI MASYARAKAT KOTA BOGOR TERHADAP NILAI KENYAMANAN UDARA (The Orientation of Bogor's Society towardValue of Air Amenity)Andry Saputra, Ricky Avenzora, Dudung Darusman & Rachmad Hermawan ...................
AGROFORESTRI KALIWU DI SUMBA: SEBUAH TINJAUAN SOSIOLOGIS (Agroforestry Kaliwu in Sumba: A Sociological Perspective)Budiyanto Dwi Prasetyo ..............................................................................................................
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI KEHUTANAN
Terbit : Desember 2016
Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini bolehdiperbanyak tanpa ijin dan biaya.
UDC(OSDCF) 630*563Yonky Indrajaya & Satria Astana
Daur Optimal Tegakan Gmelina pada Dua Proyek Karbon: Memperpanjang Daur dan Aforestasi
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3, hal. 145-154.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daur optimal tegakan gmelina pada dua proyek karbon: memperpanjang daur dan aforestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Hartman yaitu maksimasi keuntungan dengan sumber pendapatan dari kayu dan jasa lingkungan penyerapan karbon. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa harga karbon akan memengaruhi daur optimal tegakan gmelina pada proyek karbon VCS memperpanjang daur tebang. Sementara itu, pada proyek aforestasi VCS, tingkat harga karbon tidak memengaruhi daur optimal Faustmann. Nilai NPV proyek aforestasi relatif lebih tinggi dibandingkan nilai NPV proyek memperpanjang daur tebangan.
Kata kunci: Daur optimal; gmelina; proyek karbon; NPV.
UDC(OSDCF) 630*907.11Wahyudi Isnan
Harga Optimal Tiket Masuk Wisata Alam Bantimurung, Sulawesi Selatan
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3, hal. 155-163.
Penelitian bertujuan untuk menganalisis harga optimal tiket masukdan kesediaan membayar pengunjung wisata alam Bantimurung, Sulawesi Selatan dengan metode biaya perjalanan berbasis zona. Jumlah sampel sebanyak 117dengan metode convenience sampling. Analisis dilakukan dengan membuat fungsi permintaan wisata, kemudian mensimulasikan harga tiket masuk ke dalam fungsi persamaan permintaan wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga optimal tiket masuk pada hargaRp. 75.000 dengan penerimaan sebesar Rp. 18.230.700.000. Rata-rata dari pengunjung bersedia membayar Rp. 118.032 dengan surplus konsumen Rp. 43.032. Kenaikan harga tiket masuk berimplikasi pada penerimaan optimal bagi pengelola dan ruang yang lebih luas bagi pengunjung dalam menikmati wisata alam Bantimurung.
Kata kunci: Wisata alam Bantimurung, harga optimal, kesediaan membayar.
UDC(OSDCF) 630*907Nugroho Adi Utomo & Santun R.P. Sitorus
Sinergi Tata Ruang terhadap Pelaksanaan REDD+: Studi Kasus di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3, hal. 165-176.
Salah satu upaya mitigasi perubahan iklim adalah REDD+. Kabupaten Katingan terletak di provinsi pilot percontohan REDD+, Kalimantan Tengah. Masalah penurunan luasan hutan dan ekspansi perkebunan dan pertanian perlu memperhatikan tata ruang agar REDD+ berjalan, oleh karenanya perlu penelitian tata ruang dan REDD+. Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan lahan, menganalisis inkonsistensi penggunaan lahan, menganalisis isi kebijakan, menganalisis pendapat stakeholder dan penyempurnaan RTRW. Hasil penelitian mendukung inisiatif REDD+ dapat berjalan di Kabupaten Katingan dengan penyempurnaan RTRW, melalui sinkronisasi inisiatif REDD+ dan RTRW Kabupaten serta akomodasi ruang inisiatif REDD+ pada kawasan lindung dan sebagian kawasan budidaya.
Kata kunci: Penggunaan lahan; penataan ruang; preferensi stakeholder; REDD+; Katingan.
UDC(OSDCF) 630*111.83Andry Saputra, Ricky Avenzora, Dudung Darusman & Rachmad Hermawan
Orientasi Masyarakat Kota Bogor terhadap Nilai Kenyamanan Udara
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3, hal. 177-187.
Partisipasi masyarakat diperlukan untuk merealisasikan program ameliorasi iklim mikro. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi masyarakat, indeks kenyamanan udara, dan nilai willingness to pay (WTP) masyarakat. Data diperoleh melalui kuesioner dan survei lapangan kemudian dianalisis statistik dan deskriptif. Penelitian menunjukkan setiap kelurahan memiliki permasalahan berbeda terkait dengan faktor penyebab degradasi kenyamanan udara yang didukung oleh nilai THI tidak nyaman dan persepsi dari masyarakat bahwa terjadi peningkatan suhu udara dan kelembapan udara. Nilai WTP sejumlah Rp 12.413/KK/bulan menjadi solusi dalam ameliorasi iklim mikro Kota Bogor.
Kata kunci: Kenyamanan udara; Kota Bogor; Iklim mikro; willingness to pay.
ISSN: 1979-6013eISSN: 2502-4221
UDC(OSDCF) 630*26Budiyanto Dwi Prasetyo
Agroforestri Kaliwu di Sumba: Sebuah Tinjauan Sosiologis
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3, hal. 189-199.
Agroforestri merupakan salah satu sistem pengelolaan lahan yang populer di Indonesia terutama di daerah berlahan kritis dan kering. Sistem ini sangat membantu masyarakat desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahannya melalui fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Masyarakat tradisional Sumba mengenal sistem agroforestri dengan nama Kaliwu. Sistem ini telah diterapkan sejak lama dan merupakan bagian dari pengetahuan asli masyarakat Sumba dalam mengelola lahan secara turun temurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek sosiologis di balik praktek kaliwu yang disinyalir manjadi faktor penentu kelestarian sistem ini dari generasi ke generasi. Penelitian dilakukan selama setahun pada 2009 di Desa Waimangura, Pulau Sumba. Pengumpulan data dilakukan melalui survey sosial terhadap 30 responden, wawancara, observasi, dan studi pustaka. Data dan informasi yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara sosiologis, kaliwu merupakan sebuah sistem pengetahuan pengelolaan lahan yang otentik dan terwariskan secara turun-temurun pada masyarakat Sumba. Kaidah-kaidah sosial (ketaatan pada nilai tradisional, pembagian kerja, manajemen konflik) dan lembaga sosial kelompok tani menjadi faktor sosial yang menopang keberlanjutan kaliwu di tengah masyarakat.
Kata kunci: Agroforestri, tradisional, kaliwu, perspektif sosiologis, sumba.
FORESTRY SOCIO AND ECONOMIC RESEARCH JOURNAL
Date of issue : December 2016
The discriptors given are keywords. The abstract sheet may be reproducedwithout permission or charge.
UDC(OSDCF) 630*563Yonky Indrajaya & Satria Astana
The Optimal Rotations of Gmelina Stand on Two Carbon Projects: Lengthening Rotation and Afforestation
Forestry Socio and Economic Research Journal Vol. 13 No. 3, p. 145-154.
This study aimed to analyze the optimal rotation of gmelina forest on two carbon projects: Lengthening rotation and afforestation. The method used was by using Hartman method, by maximizing profit with the revenue source from timber and carbon seqeustration project. The results showed that carbon price will affect the optimal rotation for the project of lengthening forest rotation. Meanwhile, for afforestation project, carbon price level had no effect to the optimal rotation of gmelina stands. The NPV value of the afforestation project was relatively higher compare to the NPV value of the lengthening forest rotation.
Keywords: Optimal rotation; gmelina; carbon projec;, NPV.
UDC(OSDCF) 630*907.11Wahyudi Isnan
Optimal Price of Admission Bantimurung Natural Park, South Sulawesi
Forestry Socio and Economic Research Journal Vol. 13 No. 2, p. 85-106.
The study aims to analyze optimal price of admission and willingness to pay for visitors of Bantimurung natural park (NP), South Sulawesi. Number of samples taken 117by the method of convenience sampling. Analysis were done by creating a tourism demand function which simulated the price of admission into the function of tourist demand equation. The results showed that the optimal price of admission is at the price of Rp. 75,000. At the optimal price of admission Rp. 75,000 the NP would earn revenues of Rp. 18.2307 billion. Value of willingness to pay average of visitors is Rp. 118,032 and consumer surplus of Rp. 43,032.The increase in the price of admission implications for optimal revenue to managers and greater space for visitors to enjoy the Bantimurung NP.
Keywords: Bantimurung natural park, optimal price, willingness to pay.
UDC(OSDCF) 630*907Nugroho Adi Utomo & Santun R.P. Sitorus
Synergy of Spatial Planning for REDD+ Implementation at Katingan District, Central Kalimantan
Forestry Socio and Economic Research Journal Vol. 13 No. 3, p. 165-1176.
One effort to mitigate climate change is by perform the REDD+. Katingan District is located in the REDD+ pilot project Province of Central Kalimantan. Expansion of plantation and agriculture sectors growing rapidly. Further study on spatial plan and REDD+ need to be done. This study aims to analyze land use change, land use inconsistencies, contents of policies, preferences of stakeholder, and improvement of spatial plan. The results of the study are support the REDD+ initiatives implemented in RTRW, through synchronization of REDD+ initiatives and space allocation for REDD+ initiatives should be placed in protected areas and partially in cultivated areas.
Keywords: Land use; spatial planning; stakeholder preferences; REDD+; Katingan.
UDC(OSDCF) 630*111.83Andry Saputra, Ricky Avenzora, Dudung Darusman & Rachmad Hermawan
The Orientation of Bogor’s Society toward Value of Air Amenity
Forestry Socio and Economic Research Journal Vol. 13 No. 3, p. 177-187.
Public participation is needed in realizing micro-climate amelioration program. This research aims to analyze public perception, air amenity index, and willingness to pay (WTP). Data was collected through questionnaires and field survey then analyzed statistically and descriptively. The research showed that each village facing different problems related to the causes of the air amenity degradation that supported by the value of Temperature Humidity Index which was uncomfortable and according to the public perception that there was an increasing of the air temperature and humidity. The value of WTP was Rp 12,413/family/month become solution of the micro-climate amelioration in Bogor City.
Keywords: .Air amenity; Bogor City; micro-climate; willingness to pay
ISSN: 1979-6013eISSN: 2502-4221
UDC(OSDCF) 630*26Budiyanto Dwi Prasetyo
Agroforestry Kaliwu in Sumba: A Sociological Perspective
Forestry Socio and Economic Research Journal Vol. 13 No. 3, p. 189-199.
Agroforestry is a land management system that is already popular in Indonesia. Such system has helped farmers to increase their agricultural production, social life, and ecological stability. Traditional community in Sumba has applied agroforestry since long time ago and known as Kaliwu. This becomes one of indigenous knowledge, as Kaliwu is a system that is socially constructed through an intensive interaction between local people and its environment and transmitted from generation to generation. This study sought to convey sociological aspects that are suspected as the key factors that made this system socially existed up until now. The study was conducted a year in 2009 in Desa Waimangura, Sumba Island. This is a social research, which employs several data collection techniques such as social survey towards 30 respondents, in-depth interview, observation, and literature review. Data have been analyzed through quantitative and qualitative procedures. The results indicated that sociologically, Kaliwu is a knowledge system of traditional land management that has been constructed along with the socio-historical practices experienced by indigenous people. Social norms (adherence to traditional values, division of labour systems, conflict management) and social institution such as farmer group become the social factors that play significant role to make kaliwu sustainable.
Keywords: Agroforestry, traditional, kaliwu, sociological perspective, sumba.
145JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 145-154
DAUR OPTIMAL TEGAKAN GMELINA PADA DUA PROYEK KARBON: MEMPERPANJANG DAUR DAN AFORESTASI
(The Optimal Rotations of Gmelina Stand on Two Carbon Projects: Lengthening Rotation and Afforestation)
Yonky Indrajaya & Satria Astana1 2
1Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Agroforestry, Jl. Raya Ciamis-Banjar km 4, Ciamis, IndonesiaEmail: [email protected]
2Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan IklimJl. Gunung Batu No.5, Bogor, Indonesia
Email: [email protected]
Diterima 22 November 2016, direvisi 25 November 2016, disetujui 12 Desember 2016
ABSTRACT
Forest plantation may contribute economically and socially as a provider of wood raw materials for industry and providing jobs for local people. In addition, forest plantation may also contribute as watershed protection and carbon sequestration. Projects on carbon sequestration from plantation forest can be conducted in two types: (1) afforestation and (2) lengthening forest rotation. One of the potential carbon markets operationalized in the field is voluntary market with Verified Carbon Standard mechanism. This study aimed to analyze the optimal rotations of gmelina forests on two carbon projects: lengthening rotation and afforestation. The method used in this study was by using Hartman model ( ) by maximizing profit with the revenue source from timber and carbon sequestration i.e. Faustmannproject. The results of this study showed that carbon price will affect the optimal rotation for lengthening forest rotation of VCS project. Meanwhile, for VCS afforestation project, carbon price had no effect on the optimal rotation on gmelina forest. The NPV value of afforestation project was relatively higher than that of NPV value of lengthening forest rotation project, since the amount of carbon that can be credited relatively higher in afforestation project.
Keywords: Optimal rotation; gmelina; carbon projec; NPV.
ABSTRAK
Hutan tanaman dapat berkontribusi secara ekonomi dan sosial yaitu penyedia bahan baku kayu untuk industri dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu, hutan tanaman dapat pula berkontribusi dalam pengaturan tata air dan penyerapan karbon. Proyek perdagangan karbon untuk hutan tanaman dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain dengan pembangunan hutan tanaman baru di lahan terbuka ( ) dan aforestasimemperpanjang daur tebangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daur optimal tegakan gmelina pada dua proyek karbon: memperpanjang daur dan aforestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Faustmann yang dimodifikasi (yaitu Hartman) yaitu maksimasi keuntungan dengan sumber pendapatan dari kayu dan jasa lingkungan penyerapan karbon. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa harga karbon akan memengaruhi daur optimal tegakan gmelina pada proyek karbon VCS memperpanjang daur tebang. Sementara itu, pada proyek aforestasi VCS, tingkat harga karbon tidak memengaruhi daur optimal Faustmann. Nilai NPV proyek aforestasi relatif lebih tinggi dibandingkan nilai NPV proyek memperpanjang daur tebangan karena jumlah karbon yang dapat dikreditkan relatif lebih tinggi pada proyek aforestasi.
Kata kunci: .Daur optimal; gmelina; proyek karbon; NPV
146
Pada umumnya, penentuan daur tebang hutan tanaman termasuk hutan rakyat dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, apabila hanya mempertimbangkan kayu sebagai sumber pendapatan (Indrajaya & Siarudin, 2013; Indrajaya & Siarudin, 2015a). Apabila tidak hanya kayu yang diperhitungkan sebagai sumber pendapatan (misalnya ditambah penjualan jasa lingkungan karbon), maka daur optimal tegakan hutan dapat berubah tergantung pada besarnya pendapatan yang diperoleh dari penjualan jasa lingkungan tegakan hutannya dan waktu dilakukannya pembayaran jasa lingkungan tersebut. Besarnya pendapatan dan tata waktu penjualan jasa lingkungan karbon tersebut dipengaruhi oleh mekanisme yang digunakan dalam penjualan jasa lingkungan karbon.
Penelitian tentang pengaruh penjualan jasa lingkungan karbon terhadap daur optimal tegakan hutan tanaman telah banyak dilakukan di berbagai tempat di dunia pada berbagai jenis pohon hutan tanaman (Asante & Armstrong, 2016; Diaz-Balteiro & Rodriguez, 2006, Foley & Galik, 2009; Hoel, Holtsmark, 2014; Huang & Kronrad, 2006; Köthke & Dieter, 2010; Zhou & Gao, 2016). Olschewski and Benitez (2010) dalam penelitiannya di Ekuador pada jenis Cordia alliodora menemukan bahwa proyek aforestasi CDM dapat memperpanjang daur hingga dua kali lipat dibandingkan apabila tanpa proyek karbon. Sementara itu, Galinato and Uchida (2011) menemukan bahwa pada jenis yang cepat tumbuh, daur relatif tidak elastis terhadap harga karbon dibandingkan dengan jenis yang lambat tumbuh. Pada proyek CDM, jumlah karbon yang dapat dikreditkan adalah jumlah karbon total dari suatu tegakan hutan proyek aforestasi. Sementara itu, pada proyek karbon sukarela, jumlah karbon yang dapat dikreditkan pada proyek aforestasi adalah jumlah rata-rata karbon tersimpan dalam satu daur tebang. Jumlah karbon dapat memengaruhi daur optimal tegakan hutan tanaman. Penelitian tentang tambahan pendapatan dari jasa lingkungan karbon pada hutan tanaman ini belum banyak dilakukan di Indonesia. Padahal, penelitian ini cukup penting untuk dilakukan mengingat potensinya dalam memberikan tambahan pendapatan bagi petani pengelola hutan tanaman dan perbaikan lingkungan.
I. PENDAHULUAN
Keberadaan hutan rakyat penting sebagai salah satu pemasok kayu di Indonesia, karena semakin rendahnya produksi kayu dari hutan alam dan belum optimalnya pembangunan hutan tanaman (Astana et al., 2014; Diniyati & Awang, 2010). Salah satu jenis hutan rakyat yang banyak diusahakan oleh masyarakat di wilayah Priangan Timur (Kota Banjar dan Kabupaten Tasikmalaya) adalah jenis gmelina (Gmelina arborea Roxb.). Alasan pemilihan jenis gmelina oleh masyarakat adalah karena harga kayunya yang relatif tinggi (kurang lebih sama dengan jenis sengon) dengan tingkat pertumbuhan yang relatif cepat (Roshetko, Mulawarman, & Purnomosidhi, 2004). Karena kualitas dan penampakannya yang relatif sama dengan sengon, kayu gmelina dapat mensubstitusi kayu sengon pada beberapa keperluan.
Selain berfungsi untuk memproduksi kayu, hutan rakyat sebagai kumpulan pohon hutan dapat pula berfungsi lingkungan, yaitu dalam pengaturan tata air dan penyerapan karbon. Penjualan jasa lingkungan penyerapan karbon telah cukup lama digagas oleh para pihak dan telah diimplemen-tasikan di beberapa negara di dunia melalui Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism-CDM) sektor kehutanan yaitu dengan proyek aforestasi dan reforestasi. Selain itu, keberadaan pasar karbon sukarela cukup penting keberadaannya di dunia dengan pertumbuhan yang cukup tinggi (Peters-Stanley, Hamilton, & Yin, 2012). Salah satu mekanisme dalam pasar karbon sukarela adalah VCS (Verified Carbon Standard) yang telah banyak diimplemen-tasikan sejak 2008 (Kollmuss, Lazarus, Lee, LeFranc, & Polycarp, 2010). Proyek karbon hutan tanaman yang mungkin dilakukan oleh pengelola hutan tanaman adalah dengan cara meningkatkan jumlah karbon tersimpan rata-rata dalam setiap daurnya (Verified Carbon Standard, 2013a, 2013b) dengan cara aforestasi atau memperpanjang daur tebang. Kedua cara tersebut dapat dilakukan tergantung dari kondisi lahan yang ada. Pada kondisi dimana hutan rakyat gmelina telah dikembangkan secara masif, memperpanjang daur tebang tentu lebih tepat dilakukan. Sementara itu, apabila lahan kosong atau padang rumput tersedia cukup luas, maka proyek aforestasi mungkin lebih tepat untuk dikembangkan.
Daur Optimal Tegakan Gmelina pada Dua Proyek Karbon: ..... (Yongky Indrajaya & Satria Astana)
Keuntungan maksimum dari penjualan kayu dan jasa lingkungan karbon secara matematis adalah:
Jasa lingkungan karbon mulai dibayarkan ketika C t> C yaitu pada saat jumlah karbon tersimpan baseline
dalam biomassa tegakan gmelina lebih tinggi daripada rata-rata karbon tersimpan dalam bio-massa baseline. Pembayaran jasa lingkungan karbon dihentikan pada saat akumulasi karbon tersimpan dalam biomassa tegakan gmelina sama dengan rata-rata karbon tersimpan dalam biomassa tegak-an gmelina dalam satu daur proyek, yaituPenelitian ini menggunakan dua jenis proyek karbon, yaitu: (1) aforestasi dimana pembangunan hutan tanaman gmelina dimulai dari padang rumput dengan nilai baseline sebesar 1,6 ton CO /ha (IPCC, 2006), dan (2) memperpanjang 2
daur tebang gmelina (yaitu baseline merupakan rata-rata karbon tersimpan dalam biomassa tegakan gmelina yang dikelola apabila hanya memper-timbangkan kayu sebagai sumber pendapatan). Berdasarkan penelitian Indrajaya & Siarudin (2015a), daur optimal gmelina adalah 10 tahun dengan rata-rata jumlah karbon tersimpan dalam tegakan gmelina adalah 62,70 ton CO /ha. 2
Penelitian ini mengasumsikan tidak terjadinya kebocoran (leakage) dalam proyek karbon.
Berat biomassa tegakan gmelina dihitung dengan menggunakan persamaan allometrik yang dibuat oleh (Agus, 2001), yaitu:
2 0.99 AGB (t) = 0.06 (D(t) H(t)) (4)
Dimana AGB merupakan berat biomassa pohon (kg/pohon), D merupakan diameter setinggi dada
(cm) pada tahun ke- t dan H merupakan tinggi total
(meter) pada tahun ke- t. Model estimasi pertum-
buhan gmelina yang digunakan dalam penelitian ini adalah merujuk pada model pertumbuhan yang telah digunakan sebelumnya (Indrajaya & Siarudin, 2015a; Indrajaya & Siarudin, 2015b; Siarudin, Indrajaya, Suhaendah, & Badrunasar, 2014). (Fraksi karbon dalam biomassa adalah sebesar 0,47 (IPCC, 2006). Jumlah karbondioksida yang tersimpan dalam biomassa dihitung dengan mengalikan jumlah karbon tersimpan dalam biomassa dengan rasio berat molekul CO dan unsur 2
C, yaitu 44/12.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daur optimal tegakan gmelina pada dua proyek karbon: memperpanjang daur dan aforestasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam pengembangan hutan rakyat untuk mitigasi perubahan iklim.
II. METODE PENELITIAN
A. Daur Faustmann
Daur Faustmann ditentukan berdasarkan nilai kiwari atau Net Present Value (NPV) dari tegakan gmelina yang dihitung untuk semua rotasi/rotasi tak terhingga (Indrajaya & Siarudin, 2015a) dimana kayu menjadi satu-satunya sumber pendapatan dari tegakan hutan tanaman gmelina. Pada penelitian ini, karena proses verifikasi dan pembayaran jasa lingkungan karbon dilakukan tahunan, maka variabel waktu yang digunakan adalah variabel diskrit. Persamaan Faustmann untuk menentukan daur optimal secara finansial yaitu:
Keterangan:3p = harga kayu net biaya penebangan per m
3(Rp/m )K = biaya pembangunan hutan tanaman gmelina
(Rp/ha), dani = suku bunga riil (%)
Daur optimal Faustmann (T) diperoleh ketika nilai NPV maksimum.
B. Daur Hartman
Daur Hartman merupakan modifikasi dari Faustmann dengan tambahan pendapatan dari penjualan jasa lingkungan karbon. NPV karbon merupakan jumlah pembayaran jasa lingkungan penyerapan karbon yang dibayarkan pada tahun tertentu hingga mencapai batas maksimum jumlah karbon yang dapat dikreditkan:
p = harga karbon (Rp/ton Co )c 2
C = jumlah karbon tersimpan dalam biomassa t
tegakan gmelina pada waktu c (ton CO )2
147
NPVkayu = ps(T) – K(1+r)T
(1) (1+r)T–1
NPVkarbon = (2) ST
t=1pcCt(1+r)T-t
(1+r)T–1
JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 145-154
kayu+karbonmax NPV =T
T T–tps(T)–K(1+r) +å p C (1+r)t=1 c t
T–1(1+r)
T
å C = Ct=1 t T
T –
(3)
Data ekonomi pengelolaan hutan tanaman gmelina yang digunakan merujuk pada Indrajaya & Siarudin (2015a), yaitu: (1) biaya penanaman gmelina adalah sebesar Rp14.590.000 per ha, (2)
3harga kayu per m adalah Rp500.000, (3) biaya pemanenan sebesar Rp50.000, dan (4) suku bunga riil yang digunakan adalah sebesar 4%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar tahun 2015 yaitu Rp13.389 (World Bank, 2016).
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan April 2016 di Kabupaten Banjar dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Penelitian ini merupakan lanjutan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Indrajaya & Siarudin (2015a) dan Indrajaya & Siarudin (2015b).
B. Karbon Tegakan Gmelina dalam proyek VCS
Verified Carbon Standard (VCS) merupakan salah satu pasar karbon sukarela berdasarkan sistem baseline and crediting yang menggunakan mekanisme sertifikasi bahwa proyek menyebabkan penurunan emisi gas rumah kaca secara aktif (Dewan Nasional Perubahan Iklim, 2013). Pada umumnya proyek yang mengikuti VCS adalah proyek yang tidak dapat mengikuti CDM, karena tidak memenuhi syarat CDM atau karena tidak adanya metodologi dalam CDM. Dewan Nasional Perubahan Iklim (2013) melaporkan bahwa hingga tahun 2013, proyek VCS yang telah dikembangkan di Indonesia adalah sebanyak 11 proyek, dan telah menghasilkan 2,9 juta VCU (Verified Carbon Unit).
Dalam penelitian ini, proyek karbon yang dianalisis adalah memperpanjang daur tebangan tegakan gmelina (A) dan pembangunan tegakan gmelina di tanah kosong/aforestasi (B). Oleh karenanya, baseline yang digunakan pun berbeda untuk dua proyek karbon tersebut. Untuk proyek A, baseline yang digunakan adalah jumlah karbon rata-rata tersimpan dalam biomassa tegakan gmelina apabila hanya mempertimbangkan kayu sebagai satu-satunya pendapatan dari tegakan gmelina,
yaitu tegakan pada daur Faustmann. Daur Faustmann tegakan gmelina berdasarkan Indrajaya and Siarudin (2015a) adalah 10 tahun, yaitu dengan nilai Land Expectation Value (LEV) sebesar Rp57.979.645. Jumlah rata-rata karbon tersimpan dalam biomassa tegakan gmelina daur 10 tahun adalah sebesar 62,70 ton CO equivalent/ha (Tabel 2
1). Sementara itu, pada proyek B, baseline diasumsikan adalah sebesar 1,6 ton CO /ha.2
Jumlah kredit karbon yang dapat dibayarkan pada proyek A disajikan dalam kolom 4 (Tabel 1). Karena proyek A merupakan proyek karbon dengan memperpanjang daur tebangan, maka jumlah karbon yang dapat dikreditkan adalah selisih rata-rata jumlah karbon tersimpan dalam biomassa setelah tahun ke-10 (kolom 5). Pada tahun ke-10 proyek A, jumlah karbon yang dapat dikreditkan adalah nol, karena jumlah karbon tersimpan dalam biomassa tegakan gmelina pada tahun ke-10 sama dengan . Semakin lama baselinedaur tebang, semakin tinggi jumlah karbon yang dapat dikreditkan, misalnya pada tahun ke-11, jumlah karbon yang dikreditkan pada proyek A adalah sebesar 4,88 ton CO /ha, sementara itu 2
pada tahun ke-20 jumlah karbon yang dapat dikreditkan adalah sebesar 36,13 ton CO /ha. Pada 2
proyek B, jumlah karbon yang dapat dikreditkan dapat dihitung mulai tahun ke-1, karena baselineyang digunakan adalah nol. Penerbitan VCU dimulai pada tahun ke-6 proyek A dan tahun ke-1 proyek B.
Tabel 2 menunjukkan detail jumlah dan waktu penerbitan VCU proyek A dan B. Proses verfikasi untuk penerbitan VCU diasumsikan dilakukan pada tahun yang sama diterbitkannya VCU. Jumlah VCU yang diterbitkan pada proyek A pada tahun ke-6 adalah sebesar 4,88 ton CO /ha. Jumlah ini 2
adalah selisih dari rata-rata karbon tersimpan dalam biomassa tegakan gmelina daur 11 tahun dengan baseline (yaitu daur 10 tahun). Memper-panjang daur selama satu tahun akan menambah jumlah CO yang tersimpan dalam biomassa 2
tegakan gmelina sebanyak 4,88 ton/ha. Sementara itu, pada proyek dengan daur 12 tahun, atau memperpanjang daur tebang selama dua tahun, maka jumlah tambahan CO yang dapat diserap 2
adalah sebanyak 9,44 ton CO yang penerbitan 2
VCUnya juga dilakukan dimulai pada tahun ke-6. Jumlah maksimum VCU maksimum yang dapat diterbitkan pada tahun ke-6 proyek A adalah sebanyak 11,81 ton CO /ha, sehingga misalnya 2
148Daur Optimal Tegakan Gmelina pada Dua Proyek Karbon: ..... (Yongky Indrajaya & Satria Astana)
149
Wak
tu
(Tim
e)
(Tah
un/
Yea
r)
CO
2 te
rsim
pan
d
alam
bio
mas
sa
di a
tas
per
muk
aan
ta
nah
(C
O2
stor
ed
in a
bove
gro
und
biom
ass)
(t
on
CO
2/h
a)
Rat
a-ra
ta C
O2
(CO
2 av
erag
e)
(to
n C
O2/
ha)
Dat
a d
asar
B
asel
ine
(t
on
CO
2/h
a)
Jum
lah
kar
bo
n k
red
it
Am
ount
of c
redi
ted
CO
2 (t
on
CO
2/h
a)
Tam
bah
an
Add
ition
ality
(t
on
CO
2/h
a)
1
2 3
4 =
2-3
5
= 1
-3
A
B
A
B
A
B
1 6,
06
6,06
62
,70
1,60
-5
6,64
4,
46
-56,
64
4,46
2 19
,85
12,9
5 62
,70
1,60
-4
9,74
11
,35
-42,
85
18,2
5
3 34
,00
19,9
7 62
,70
1,60
-4
2,73
18
,37
-28,
7032
,40
4 47
,63
26,8
8 62
,70
1,60
-3
5,81
25
,28
-15,
07
46,0
3
5 60
,41
33,5
9 62
,70
1,60
-2
9,11
31,9
9 -2
,29
58,8
1
6 72
,23
40,0
3 62
,70
1,60
-22,
6738
,43
9,53
70
,63
7 83
,02
46,1
7 62
,70
1,60
-1
6,53
44
,57
20,3
281
,42
8 92
,80
52,0
0 62
,70
1,60
-1
0,70
50
,40
30,1
091
,20
9 10
1,58
57
,51
62,7
0 1,
60
-5,1
9 55
,91
38,8
8 99
,98
10
109,
41
62,7
0 62
,70
1,60
0,
00
61,1
0 46
,71
107,
81
11
116,
32
67,5
7 62
,70
1,60
4,
8865
,97
53,6
311
4,72
12
122,
38
72,1
4 62
,70
1,60
9,
44
70,5
4 59
,68
120,
78
13
127,
63
76,4
1 62
,70
1,60
13
,71
74,8
1 64
,93
126,
03
14
132,
12
80,3
9 62
,70
1,60
17
,69
78,7
9 69
,42
130,
52
15
135,
91
84,0
9 62
,70
1,60
21
,39
82,4
9 73
,21
134,
31
16
139,
05
87,5
2 62
,70
1,60
24
,83
85,9
2 76
,35
137,
45
17
141,
58
90,7
0 62
,70
1,60
28
,01
89,1
0 78
,88
139,
98
18
143,
55
93,6
4 62
,70
1,60
30
,94
92,0
4 80
,85
141,
95
19
145,
00
96,3
4 62
,70
1,60
33
,65
94,7
4 82
,31
143,
40
20
145,
99
98,8
3 62
,70
1,60
36
,13
97,2
3 83
,29
144,
39
Tab
el 1
. C
Oeq
uiva
len
t te
rsim
pan
dal
am b
iom
assa
teg
akan
gm
elin
a da
n ju
mla
h k
redi
t C
O e
quiv
alen
t2
2
Tab
le 1
. C
O s
tore
d in
gm
elin
a fo
rest
bio
mas
s an
d th
e am
ount
of
CO
cre
dite
d2
2
Ket
eran
gan
():
A
= p
roye
k V
CS
den
gan
mem
per
pan
jan
g da
ur t
eban
gan
gm
elin
a; B
= p
roye
k V
CS
den
gan
keg
iata
n a
fore
stas
i (R
emar
kA
= V
CS
proj
ect o
f le
ngth
enin
g fo
rest
rot
atio
n of
gm
elin
a st
and;
B =
VC
S pr
ojec
t of
affo
rest
atio
n)Su
mb
er (
):
Sour
ceD
ata
seku
nde
r di
ola
h (
Ana
lysi
s of
sec
onda
ry d
ata)
Per
ubah
an ju
mla
h
CO
2 te
rsim
pan
ka
ren
a p
ertu
mbu
han
(C
hang
es o
f CO
2 du
e to
gro
wth
of g
mel
ina
stan
d)
(to
n C
O2/
ha)
Un
it k
arb
on
te
rver
ifik
asi
yan
g te
rsed
ia
pad
a ta
hun
ke-
t (V
erifi
ed
carb
on u
nit
av
aila
ble
at y
ear
t)
(to
n C
O2/
ha)
6 7
A
B
A
B
0,0
6,06
0,
0 6,
06
13,7
9 13
,79
0,0
13,7
9
14,1
5 14
,15
0,0
14,1
5
13,6
3 13
,63
0,0
13,6
3
12,7
912
,79
0,0
12,7
9
11,8
1 11
,81
11,8
1 11
,81
10,8
010
,80
10,8
010
,80
9,78
9,78
9,
789,
78
8,78
8,78
8,
78
8,78
7,83
7,83
7,
83
7,83
6,92
6,
92
6,92
6,
92
6,06
6,
06
6,06
6,
06
5,25
5,25
5,
25
5,25
4,49
4,49
4,
49
4,49
3,79
3,
79
3,79
3,
79
3,14
3,
14
3,14
3,
14
2,53
2,
53
2,53
2,
53
1,97
1,
97
1,97
1,
97
1,46
1,
46
1,46
1,
46
0,98
0,
98
0,98
0,
98
JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 145-154
150
Rot
atio
n)
Yea
r)
Un
it k
arb
on
ter
veri
fika
si p
ada
tah
un k
e-t
(VC
U in
yea
r t)
T
ota
l VC
U(t
on
CO
2/h
a)1
2 3
4 5
6 7
8 9
10
11
B
B
B
B
B
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
1 6,
06
0,00
6,
06
2 6,
06
5,30
0,00
12
,9
3 6,
06
12,3
1
0,
00
19,9
7
4 6,
06
13,7
9 5,
43
0,
00
26,8
8
5 6,
06
13,7
9 12
,14
0,
00
33,5
9
6 6,
06
13,7
9 14
,15
4,43
4,88
4,
88
40,0
3
7 6,
06
13,7
9 14
,15
10,5
7
9,44
9,
44
46,1
7
8 6,
06
13,7
9 14
,15
13,6
3 2,
77
11,8
1
1,90
13,7
1 52
,00
9 6,
06
13,7
9 14
,15
13,6
3 8,
28
11,8
1
5,88
17,6
9 57
,51
10
6,06
13
,79
14,1
5 13
,63
12,7
911
,81
0,69
9,58
21,3
9 62
,70
11
6,06
13
,79
14,1
5 13
,63
12,7
911
,81
5,56
10,8
02,
22
24
,83
67,5
7
12
6,06
13
,79
14,1
5 13
,63
12,7
911
,81
10,1
310
,80
5,40
28,0
1 72
,14
13
6,06
13
,79
14,1
5 13
,63
12,7
911
,81
11,8
110
,80
2,58
8,
33
30
,94
76,4
1
14
6,06
13
,79
14,1
5 13
,63
12,7
911
,81
11,8
110
,80
6,56
9,
78
1,
26
33
,65
80,3
9
15
6,06
13
,79
14,1
5 13
,63
12,7
911
,81
11,8
110
,80
10,2
6 9,
78
3,
74
36
,13
84,0
9
16
6,06
13
,79
14,1
5 13
,63
12,7
911
,81
11,8
110
,80
10,8
0 9,
78
2,90
6,
01
38
,40
87,5
2
17
6,06
13
,79
14,1
5 13
,63
12,7
911
,81
11,8
110
,80
10,8
0 9,
78
6,08
8,
09
40
,47
90,7
0
18
6,06
13
,79
14,1
5 13
,63
12,7
911
,81
11,8
110
,80
10,8
0 9,
78
9,02
8,
78
1,
19
42
,36
93,6
4
19
6,06
13
,79
14,1
5 13
,63
12,7
911
,81
11,8
110
,80
10,8
0 9,
78
9,78
8,
78
1,95
2,
89
44
,06
96,3
4
20
6,06
13
,79
14,1
5 13
,63
12,7
911
,81
11,8
110
,80
10,8
0 9,
78
9,78
8,
78
4,43
4,
43
45
,60
98,8
3
21
6,06
13
,79
14,1
5 13
,63
12,7
911
,81
11,8
110
,80
10,8
0 9,
78
9,78
8,
78
6,70
5,
80
46
,97
101,
10
22
6,06
13
,79
14,1
5 13
,63
12,7
911
,81
11,8
110
,80
10,8
0 9,
78
9,78
8,
78
8,77
7,
03
48
,20
103,
17
23
6,06
13
,79
14,1
5 13
,63
12,7
911
,81
11,8
110
,80
10,8
0 9,
78
9,78
8,
78
8,78
7,
83
1,87
0,
28
49,2
8 10
5,05
24
6,06
13
,79
14,1
5 13
,63
12,7
911
,81
11,8
110
,80
10,8
0 9,
78
9,78
8,
78
8,78
7,
83
3,58
1,
23
50,2
2 10
6,76
25
6,06
13
,79
14,1
5 13
,63
12,7
911
,81
11,8
110
,80
10,8
0 9,
78
9,78
8,
78
8,78
7,
83
5,11
2,
05
51,0
4 10
8,29
Tab
el 2
. Ju
mla
h k
redi
t C
O p
ada
tiap
dau
r da
n w
aktu
pen
erb
itan
VC
U2
Tab
le 2
. T
he a
mou
nt o
f C
O c
redi
t and
tim
e fo
r re
leas
ing
VC
U2
Ket
eran
gan
():
A
= p
roye
k V
CS
den
gan
mem
per
pan
jan
g da
ur t
eban
gan
gm
elin
a; B
= p
roye
k V
CS
den
gan
keg
iata
n a
fore
stas
i (R
emar
kA
= V
CS
proj
ect o
f le
ngth
enin
g fo
rest
rot
atio
n of
gm
elin
a st
and;
B =
VC
S pr
ojec
t of
affo
rest
atio
n)Su
mb
er (
):
Sour
ceD
ata
seku
nde
r di
ola
h (
Ana
lysi
s of
sec
onda
ry d
ata)
Dau
r (
(Tah
un/
A
11
12 13
14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Daur Optimal Tegakan Gmelina pada Dua Proyek Karbon: ..... (Yongky Indrajaya & Satria Astana)
151
pada daur 13 tahun, penerbitan jumlah VCU yang diterbitkan adalah sebanyak 11,81 ton CO /ha pada 2
tahun ke-6, dan 1,9 ton CO /ha pada tahun ke-7.2
Pada proyek B, karena baseline yang digunakan relatif kecil, atau pembangunan tegakan gmelina dilakukan di padang rumput, maka pada tahun ke-1 dimana tegakan gmelina mulai tumbuh, telah ada tambahan karbon tersimpan dalam biomassa di lahan tersebut, yaitu sebesar 4,46 ton CO2
equivalent per ha. Jumlah karbon yang dapat dijual dalam bentuk VCU pada proyek B lebih besar dibandingkan dengan proyek A karena pada proyek B, baselinenya relatif lebih rendah dibandingkan baseline pada proyek A. Misalnya, pada daur 11 tahun, proyek A hanya dapat menambah karbon tersimpan sebanyak 4,88 ton CO /ha, sedangkan 2
proyek B dapat menambah karbon tersimpan sebanyak 65,97.
C. Daur Optimal Tegakan Gmelina dalam Proyek Karbon
Daur optimal tegakan gmelina pada proyek karbon sangat ditentukan oleh tingkat harga karbon yang digunakan dalam perhitungan. Harga karbon yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5, 10, 20, dan 50 USD/ton CO berdasarkan laporan dari 2
Peters-Stanley et al. (2012) yang menyebutkan bahwa harga karbon dunia berada pada kisaran 0-
100 USD/ton CO . Nilai NPV dari proyek A pada 2
beberapa harga karbon disajikan dalam Tabel 3.Tabel 3 menunjukkan bahwa peningkatan harga
karbon berkorelasi positif dengan daur tebangan, yaitu semakin tinggi harga karbon daur optimal akan semakin panjang. Semakin tinggi tingkat harga karbon, semakin besar insentif untuk menunda penebangan tegakan gmelina karena semakin besarnya jumlah rata-rata karbon yang dapat tersimpan dalam biomassa tegakan gmelina untuk dijual sebagai jasa lingkungan karbon. Hasil penelitian ini kurang lebih sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrajaya and Siarudin (2015) pada hutan tanaman manglid yang juga meng-analisis pengaruh pembayaran jasa lingkungan karbon pada proyek perpanjangan daur tebang. Namun pada tingkat harga yang sama, daur tebang gmelina relatif kurang sensitif terhadap harga karbon dibandingkan dur tegakan manglid. Misalnya, pada tingkat harga 50 USD/ton CO , 2
waktu penundaan penebangan tegakan gmelina dan manglid berturut-turut adalah 6 dan 9 tahun. Hal ini terjadi karena jenis gmelina relatif cepat tumbuh dibandingkan dengan jenis manglid, dan pembayaran jasa lingkungan karbon (atau penerbitan VCU) dimulai relatif lebih cepat pada tegakan gmelina. Sementara itu, pada proyek karbon penanaman tegakan gmelina dari lahan kosong (aforestasi) hasilnya ditampilkan dalam Tabel 4.
Daur (Rotation) (Tahun/Year)
Harga karbon (Carbon price)
0 USD/tCO2 5 USD/tCO2 10 USD/tCO2 20 USD/tCO2 50 USD/tCO2
6 41.161.061 42.223.530 43.285.998 45.410.936 51.785.748
7 49.412.418 51.375.390 53.338.362 57.264.305 69.042.136
8 54.285.508 57.009.940 59.734.373 65.183.237 81.529.830
9 56.906.517 60.277.771 63.649.026 70.391.534 90.619.060
10 57.979.645 61.912.920 65.846.195 73.712.744 97.312.393
11 57.968.954 62.383.179 66.797.404 75.625.855 102.111.206
12 57.192.568 62.023.136 66.853.703 76.514.838 105.498.242
13 55.875.223 61.070.686 66.266.150 76.657.076 107.829.857
14 54.179.365 59.690.127 65.200.890 76.222.416 109.286.993
15 52.224.478 58.006.781 63.789.084 75.353.690 110.047.507
16 50.099.586 56.119.234 62.138.882 74.178.178 110.296.067
17 47.871.611 54.097.977 60.324.342 72.777.073 110.135.266
18 45.591.145 51.902.705 58.214.264 70.837.382 108.706.737
19 43.296.514 49.633.255 55.969.996 68.643.477 106.663.922
20 41.016.715 47.374.909 53.733.102 66.449.489 104.598.650
Tabel 3. NPV tegakan gmelina pada beberapa harga karbon pada proyek VCS perpanjangan daur tebang (dalam Rupiah)
Table 3. NPV of gmelina stand on different carbon prices of VCS project of lengthening forest rotation (in IDR)
Sumber ( ): Source Data sekunder diolah (Analysis of secondary data)
JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 145-154
152
Tabel 4 menunjukkan bahwa pada proyek aforestasi, daur optimal tegakan gmelina adalah sama pada tingkat harga karbon 0-50 USD/ton CO . Hal ini terjadi karena penerbitan VCU pada 2
proyek aforestasi dilakukan pada tahun ke-1, yaitu waktu dimana jumlah karbon rata-rata lebih tinggi dari . Karena dalam proyek aforestasi baseline baseline relatif kecil (yaitu1,6 ton CO /ha), sehingga pada 2
tahun pertama, VCU telah dapat diterbitkan, dengan nilai VCU terdiskon relatif lebih rendah apabila diterbitkan kemudian. Karena pertum-buhan gmelina mencapai titik maksimum pada umur 8 tahun, yang ditandai dengan nilai riap rata-rata volume tahunan tertinggi (Indrajaya & Siarudin, 2015a), dan menurun setelah 8 tahun, maka setelah umur tersebut, pertumbuhan gmelina mengalami penurunan. Sementara itu, jumlah total karbon yang dapat dikreditkan dan dapat diterbitkan VCU untuk daur 10 tahun adalah dari tahun ke-1 hingga tahun ke-6. Tahun ke-7 hingga ke-10, tidak diterbitkan VCU karena jumlah total VCU yang dapat diterbitkan telah tercapai pada tahun ke-6 (Tabel 2).
Nilai NPV pada proyek B relatif lebih tinggi dibandingkan dengan nilai NPV pada proyek A. Hal ini terjadi karena yang digunakan dalam baselineproyek B relatif lebih rendah dibandingkan dengan proyek A, sehingga jumlah karbon yang dapat dikreditkan relatif lebih besar pada proyek B dibandingkan dengan proyek A. Oleh karena itu,
apabila memungkinkan, proyek aforestasi relatif lebih menguntungkan untuk dikembangkan dibandingkan dengan proyek memperpanjang daur tebangan, karena lebih tingginya nilai NPV pada semua tingkat harga karbon.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa harga karbon akan memengaruhi daur optimal tegakan gmelina pada proyek karbon VCS memperpanjang daur tebang. Sementara itu, pada proyek aforestasi VCS, tingkat harga karbon tidak memengaruhi daur optimal Faustmann. Nilai NPV proyek aforestasi relatif lebih tinggi dibandingkan nilai NPV proyek memperpanjang daur tebangan karena jumlah karbon yang dapat dikreditkan relatif lebih tinggi pada proyek aforestasi. Penelitian ini mengasumsi-kan tidak terjadinya kebocoran ( ) dalam leakageproyek karbon.
B. Saran
Petani hutan rakyat gmelina memiliki alternatif dalam pengelolaan hutan rakyatnya apabila mempertimbangkan pendapatan tidak hanya dari kayunya, tetapi juga pendapatan lainnya, misalnya
Tabel 4. NPV tegakan gmelina pada beberapa harga karbon pada proyek VCS aforestasi (dalam Rupiah)Table 4. NPV of gmelina stand on different carbon prices of VCS project of afforestation (in IDR)
Daur (Rotation) (Tahun/Year)
Harga karbon (Carbon price)
0 USD/tCO2 5 USD/tCO2 10 USD/tCO2 20 USD/tCO2 50 USD/tCO2
1 (341.654.222) (331.514.765) (321.375.308) (301.096.395) (240.259.654)
2 (114.285.516) 104.771.080) 95.256.643) (76.227.770) (19.141.152)
3 (34.600.890) (24.223.290) (13.845.689) 6.909.513 69.175.118
4 5.046.541 15.838.706 26.630.872 48.215.203 112.968.197
5 27.597.126 38.637.986 49.678.845 71.760.565 138.005.722
6 41.161.061 52.316.744 63.472.426 85.783.792 152.717.889
7 49.412.418 60.619.673 71.826.929 94.241.439 161.484.970
8 54.285.508 65.492.324 76.699.139 99.112.771 166.353.665
9 56.906.517 68.073.641 79.240.765 101.575.012 168.577.756
10 57.979.645 69.092.421 80.205.197 102.430.748 169.107.403
11 57.968.954 68.993.820 80.018.685 102.068.417 168.217.612
12 57.192.568 68.127.426 79.062.285 100.932.001 166.541.150
13 55.875.223 66.704.666 77.534.110 99.192.997 164.169.660
14 54.179.365 64.895.936 75.612.507 97.045.650 161.345.078
15 52.224.478 62.829.282 73.434.085 94.643.692 158.272.513
Sumber ( ): Source Data sekunder diolah (Analysis of secondary data)
Daur Optimal Tegakan Gmelina pada Dua Proyek Karbon: ..... (Yongky Indrajaya & Satria Astana)
153
jasa lingkungan karbon. Simulasi perhitungan dalam penelitian ini memberikan gambaran bagaimana hutan rakyat gmelina dikelola dengan juga memperhitungkan jasa lingkungan karbon. Penanaman kayu gmelina pada padang rumput akan memberikan tambahan pendapatan yang cukup besar bagi petani tanpa harus memperpanjang daur optimalnya.
UCAPAN TERIMA KASIH ( )ACKNOWLEDGEMENT
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada M. Siarudin dan Anas Badrunasar yang telah membantu penulis dalam pengambilan data di lapangan dan analisis data. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Aris Sudomo dan Aji Winara yang terus memberikan semangat kepada penulis untuk terus berkarya.
DAFTAR PUSTAKA
Agus, C. (2001). Production and consumption of carbon by fast growing species Gmelina arborea Roxb. in tropical plantation forest. Paper presented at the Seminar on dipterocarp reforestation to restrore environ-ment through carbon sequestration, Yogyakarta.
Asante, P., & Armstrong, G. (2016). Carbon sequestration and the optimal forest harvest decision under alternative baseline policies. Canadian Journal of Forest Research, 46(5), 656-665.
Astana, S., Obidzinski, K., Riva, W. F., Hardiyanto, G., Komarudin, H., & Sukanda, S. (2014). Implikasi biaya dan manfaat pelaksanaan SVLK terhadap sektor perkayuan skala kecil. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 11(3), 175-198.
Dewan Nasional Perubahan Iklim. (2013). Mari berdagang karbon! Pengantar pasar karbon untuk pengendalian perubahan iklim. Jakarta: Dewan Nasional Perubahan Iklim.
Diaz-Balteiro, L., & Rodriguez, L. C. (2006). Optimal rotations on Eucalyptus plantations including carbon sequestrationa comparison of results in Brazil and Spain. Forest Ecology and Management, 229(1), 247-258.
Diniyati, D., & Awang, S. A. (2010). Kebijakan penentuan bentuk insentif pengembangan hutan
rakyat di wilayah Gunung Sawal, Ciamis dengan metode AHP. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 7(2), 129-143.
Foley, T. G., & Galik, C. S. (2009). Extending rotation age for carbon sequestration: a cross-protocol comparison of North American forest offsets. Forest Ecology and Management, 259(2), 201-209.
Galinato, G. I., & Uchida, S. (2011). The Effect of Temporary Certified Emission Reductions on Forest Rotations and Carbon Supply. Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue canadience d ’ a g r o e c o n o m i e , 5 9 ( 1 ) , 1 4 5 - 1 6 4 . d o i : 10.1111/j.1744-7976.2010.01203.x
Hoel, M., Holtsmark, B., & Holtsmark, K. (2014). Faustmann and the climate. Journal of Forest Economics, 20(2), 192-210.
Huang, C.-H., & Kronrad, G. D. (2006). The effect of carbon revenues on the rotation and profitability of loblolly pine plantations in East Texas. Southern Journal of Applied Forestry, 30(1), 21-29.
Indrajaya, Y., & Siarudin, M. (2013). Daur finansial hutan rakyat jabon di Kecamatan Pekenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman, 10(4), 201-211.
Indrajaya, Y., & Siarudin, M. (2015a). Daur tebang optimal hutan rakyat gmelina (Gmelina arborea Roxb.) di Tasikmalaya dan Banjar, Jawa Barat, Indonesia. Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan, 12(2), 109-116.
Indrajaya, Y., & Siarudin, M. (2015b). The effects of carbon payment on optimal rotation of gmelina forests. Paper presented at the INAFOR 3, Bogor, Indonesia.
Indrajaya, Y., & Sudomo, A. (2015). Pengaruh tambahan pendapatan jasa lingkungan karbon terhadap daur optimal tegakan manglid di Jawa Barat. Paper presented at the AFOCO Workshop "Pengembangan mata pencaharian alternatif untuk masyarakat lokal dalam upaya menghadapi dampak perubahan iklim", Bogor.
IPCC. (2006). IPCC Guideline 2006 Guidelines for national green house gas inventories: IPCC. Diunduh dari h t t p : / / w w w . i p c c -nggip.iges.or.jp/public/2006gl/
Kollmuss, A., Lazarus, M., Lee, C., LeFranc, M., & Polycarp, C. (2010). Handbook of carbon offset programs: trading systems, funds, protocols and standards:: Routledge. Diunduh dari http://sei-us.org/publications/id/203.
Köthke, M., & Dieter, M. (2010). Effects of carbon sequestration rewards on forest managementan
JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 145-154
empirical application of adjusted Faustmann formulae. Forest police economics, 12(8), 589-597.
Olschewski, R., & Benitez, P. C. (2010). Optimizing joint production of timber and carbon sequestration of afforestation projects. Journal of Forest Economics, 16(1), 1-10. doi: DOI 10.1016/ j.jfe.2009.03.002.
Peters-Stanley, M., Hamilton, K., & Yin, D. (2012). Leveraging the landscape: state of the forest carbon markets 2012. Washington, DC: Ecosystem Marketplace.
Roshetko, J. M., Mulawarman, & Purnomosidhi, P. (2004). Gmelina arborea - a viable species for smallholder tree farming in Indonesia? New Forest, 28, 207-215.
Siarudin, M., Indrajaya, Y., Suhaendah, E., & Badrunasar, A. (2014). Pemanfaatan lahan agroforestry untuk mendukung mekanisme REDD+. (Laporan Hasil Penelitian). Ciamis: Balai Penelitian Teknologi Agroforestry, Badan Litbang Kehutanan.
Verified Carbon Standard. (2013a). Agriculture, forestry and other land use (AFOLU) requirements. (VCS Version 3). Washington, DC: VCS Association.
Verified Carbon Standard. (2013b). Methodology for improved forest management through extension of rotation age (IFM ERA). (Approved VCS Methodology VM0003, Version 1.2): Verified Carbon Standard. Diunduh dari http: //database. v-c-s.org/methodologies/ methodology-improvedforest-management-hrough-extensionrotation-age-v12.
World Bank. (2016). 5. World bank indicator. 1960-201Diunduh 20 Mei 2016 dari http: //data.world bank.org/data-catalog/world-development-indicators.
Zhou, W., & Gao, L. (2016). The impact of carbon trade on the management of short-rotation forest plantations. Forest policy and economics, 62, 30-35.
154Daur Optimal Tegakan Gmelina pada Dua Proyek Karbon: ..... (Yongky Indrajaya & Satria Astana)
155JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 155-163
HARGA OPTIMALTIKET MASUK WISATA ALAM BANTIMURUNG, SULAWESI SELATAN
(Optimal Price of Admission Bantimurung Natural Park, South Sulawesi)
Wahyudi IsnanBalai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan MakassarJalan Perintis Kemerdekaan Km.16 Makassar, Sulawesi Selatan90243, Indonesia
E-mail: [email protected]
Diterima tgl 4 Agustus 2016, direvisi 14 Agustus 2016, disetujui 28 November 2016
ABSTRACT
The number of visitors to the Bantimurung natural park fluctuated allegedly due to the increase of the price of admission ticket. The aim of the study is to analyze optimal price of admission ticket and willingness of visitors to pay admission ticket to the Park. The study was conducted in Bantimurung natural park, South Sulawsi, from January to April 2013.117 number of samples was taken by using convenience sampling method. Analysis of optimal prices and the willingness of visitors to pay for ecotourism to the Park were conducted by creating tourism demand function, which then simulated the price of admission, into the equation function of tourist demand. The results showed that the optimal price of the admission ticket was at the price of Rp75,000. At the optimal price of admission ticket of Rp75,000 the Park would earn revenues of Rp18,230,700,000. An average value of the visitor willingness to pay was Rp118,032, with price of admission ticket was Rp75,000, then, the average visitor will get consumer surplus of Rp43,032. If the management of Bantimurung natural park desiring to increase the total revenue, then the price of admission ticket can be increased to be Rp75,000.
Keywords: Bantimurung natural park; optimal price; willingness to pay.
ABSTRAK
Jumlah pengunjung wisata alam Bantimurung berfluktuasi yang diduga karena kenaikan harga tiket masuk. Penelitian bertujuan untuk menganalisis harga optimal tiket masukdan kesediaan membayar pengunjung wisata alam Bantimurung. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan April 2013 di kawasan wisata alam Bantimurung, Sulawesi Selatan dengan metode biaya perjalanan berbasis zona. Pengambilan sampel dilaksanakan dengan metode convenience sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 117. Analisis harga optimal dan kesediaan membayar pengunjung wisata alamBantimurung dilakukan dengan membuat fungsi permintaan wisata yang kemudian mensimulasikan harga tiket masuk kedalam fungsi persamaan permintaan wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga optimal tiket masuk berada pada harga Rp75.000. Pada harga optimal tiket masuk sebesar Rp75.000 diperoleh penerimaan sebesar Rp18.230.700.000. Nilai kesediaan membayar rata-rata dari pengunjung adalah sebesar Rp118.032, dengan harga tiket masuk sebesar Rp75.000 maka, rata-rata pengunjung akan mendapatkan surplus konsumen sebesar Rp43.032. Jika yang diinginkan oleh pengelola adalah kenaikan jumlah penerimaan, maka harga tiket masuk dapat dinaikkan menjadi Rp75.000.
Kata kunci: Wisata alam Bantimurung; harga optimal; kesediaan membayar.
I. PENDAHULUAN
Hutan sebagai penyedia jasa lingkungan seperti tempat rekreasi alam, dapat memberikan fungsi ekosistem alam maupun buatan yang nilai dan manfaatnya akan dirasakan oleh para pemangku kepentingan ( ). Manfaat ekosistem hutan stakeholdertidak hanya untuk pemilik hutan, tetapi juga untuk
masyarakat luas . (Brey, Riera, & Mogas, 2007)Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dapat berupa usaha rekreasi hutan (wisata alam), olah raga tantangan, pemanfaatan air, perdagangan karbon ( ) dan penyelamatan hutan dan carbon tradelingkungan.
Perkembangan pariwisata mengalami kemajuan pesat seiring dengan laju pertambahan jumlah
156Harga Optimal Tiket Masuk Wisata Alam Bantimurung, Wahyudi Isnan ..... ( )
penduduk, peningkatan standar dan kualitas hidup yang diikuti denganpendapatan per-kapita meningkatsehingga mengakibatkan kebutuhan akan wisata cenderung meningkat. Menurut Douglass (1982) setelah masa perang dunia ke-2 berakhir, terutama di negara-negara dimana perekonomian mulai berkembang, kebutuhan akan rekreasi sangat dirasakan dan bergantung pada rekreasi alam. Peningkatan permintaan jasa wisata alam akan berakibat terhadap peningkatan kebutuhan tempat wisata, transportasi, sarana prasarana wisata dan sektor pendukung lainnya.
Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pengusahaan wisata alam, yang dapat dilakukan di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. Tempat wisata di alam terbuka dengan sifat alamiah dan keaslian yang relatif masih dominan seperti taman wisata alam, hutan kota, cagar alam, taman hutan raya, taman nasional, taman buru, sungai, danau, taman laut dan tempat wisata alam lainnya cenderung merupakan pilihan dari konsumen wisata.Hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari 206 juta orang berusia 15 tahun ke atas memilih rekreasi di luar ruangan dan sebagian besar melakukan wisata berbasis alam terutama hutan dan taman (Cordell, Betz, & Green, 2002).
Salah satu kawasan wisata alam yang terkenal di Sulawesi Selatan adalah kawasan wisata alam Bantimurung yang sebelumnya adalah taman wisata alam yang kini masuk dalam wilayah Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Kawasan wisata alam Bantimurung memiliki objek wisata berupa lembah bukit kapur yang curam dengan vegetasi tropis, air terjun, dan gua yang merupakan habitat beragam spesies flora dan fauna, bahkan kawasan wisata alam Bantimurung oleh Alfred Russel Wallace dijuluki sebagai The Kingdom of Butterfly (kerajaan kupu-kupu).
Pendapatan dari hasil penjualan tiket masuk pada kawasan wisata alam Bantimurung bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting mengingat objek wisata ini tidak pernah sepi dari pengunjung, namun perkembangan terakhir jumlah pengunjung di wisata alam ini menunjukkan jumlah pengunjung yang fluktuatif. Menurut Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (2012), pada tahun 2011 jumlah pengunjung mencapai 601.597 pengunjung,
sedangkan pada tahun 2012 jumlah pengunjung menurun menjadi 557.563 pengunjung (Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, 2013). Hal ini diduga akibat kenaikan harga karcis masuk kawasan wisata alam yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp10.000 per orang naik menjadi Rp15.000 per orang pada tahun 2012.Besarnya tarif pungutan masuk ke hutan wisata berpengaruh terhadap jumlah pengunjung dan pendapatan pengusahaan ekowisata (Karyono & Muttaqin, 2003).
Sumberdaya lingkungan selalu dihadapkan dengan masalah keterbatasan informasi tentang harga, biaya dan kuantitas yang dikonsumsi. Oleh karena itu, manfaat dan biaya sumberdaya ini sulit untuk ditentukan (Nuva, Shamsudin, Radam, & Shuib, 2009). Davis & Johnson (1987) menge-mukakan bahwa besarnya nilai manfaat sumber-daya hutan sangat tergantung pada sistem penilaian yang dianut. Sebagai suatu produk yang tidak memiliki standar harga pada pasar normal, wisata alam Bantimurung perlu dianalisis harga tiket masuk demikian pula kesediaan membayar pengunjung. Tulisan ini bertujuan untuk meng- analisis berapa harga optimal tiket masuk dan kesediaan membayar pengunjung di kawasan wisata alam Bantimurung. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan taman nasional khususnya dalam penentuan harga tiket masuk.
II. METODE PENELITIAN
Penelitian harga optimal tiket masuk ini dilakukan dengan metode biaya perjalanan berbasis zona ( ) dengan zona travel cost methodmensimulasikan harga tiket masuk pada persamaan permintaan wisata (Sudarmalik, 1995; Utami & Hardiyansyah, 2012). Pembagian zona wilayah asal pengunjung menurut wilayah administrasi daerah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.
A. Waktu dan Tempat
Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan April 2013 di kawasan wisata alam Bantimurung Taman Nasional (TN) Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.
157JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 155-163
B. Metode Pengambilan Sampel
Pengambilan sampel dilaksanakan meng-gunakan metode . Jumlah sampel convenience samplingyang diambil merujuk pada rumus Slovin (Sevilla, Ochave, Punsalan, Regala, & Uriarte, 2006). Angka jumlah pengunjung wisata alam Bantimurung pada tahun 2012 adalah sebesar 557.563 orang. Tingkat ketelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 90% atau dengan 10%, maka margin errorjumlah responden yang harus diambil untuk mewakili populasi adalah minimal sebesar 117 responden.
C. Pengumpulan Data
Data yangdikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilaksanakan melalui wawancara dengan meng-gunakan daftar pertanyaan ( ) kepada questionerpengunjung wisata alam Bantimurung. Data primer adalah variabel sosial ekonomi yang terdiri dari biaya perjalanan, umur, pendapatan, pendidikan pengunjung dan lama kunjungan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dinas pariwisata, dinas kehutanan, dinas pendapatan setempat, TN Bantimurung Bulusaraung, Badan Pusat Statistik serta instansi terkait lainnya. Data sekunder berupa jumlah pengunjung pada tahun 2005 sampai dengan 2012, jumlah penduduk dari masing-masing zona yang disampling serta data perubahan harga tiket masuk kawasan wisata alam Bantimurung.
D. Analisis Data
Analisis data melalui beberapa tahapan sebagai berikut:1. Menentukan persamaan permintaan wisata alam
Bantimurung
Untuk menentukan persamaan permintaan wisata digunakan kurva permintaan Marshal (Ginoga & Lugina, 2007) dengan membuat model persamaan regresi yang merupakan hubungan antara jumlah pengunjung per 1.000 penduduk daerah asal (zona) pengunjung yang mencerminkan permintaan atau konsumsi dengan biaya perjalanan yang mencerminkan harga dan variabel sosial ekonomi lainnya. Model regresinya adalah sebagai berikut:
Y = X + X X X X (1) β +β β +β +β +β0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
Keterangan: Y = jumlah pengunjung per1.000 penduduk β0 = intersep β1,2,…,5 = koefisien regresiX = biaya perjalanan rata-rata (Rp)1
X = umur pengunjung (tahun)2
X = pendapatan pengunjung (Rp/bulan)3
X = pendidikan/lama menempuh pen-4
didikan (tahun)X = lama kunjungan (jam)5
Jumlah pengunjung per 1.000 penduduk (Y) per tahun dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Yi = (2)
Keterangan: Yi = jumlah pengunjung per 1.000 penduduk per
tahun zona iJsi = jumlah sampel pengunjung dari zona iJSt = jumlah total sampel yang dipilihJpi = jumlah penduduk zona i pada tahun 2012JP = jumlah pengunjung ke wisata alam
Bantimurung pada tahun 2012
Selanjutnyaadalahmenentukan intersep baru β ' 0
fungsi permintaan dimana asumsi keadaan variabel bebas lainnya (X X Xn) adalah tetap (ceteris 2, 3,…..,
paribus).Y = β + β X + β X + ….. + β X (3)0 1 1 2 2 n n
Y = (β + β X + ….. + β X ) + β X (4)0 2 2 n n 1 1
Y = β ' + β X (5)0 1 1
2. Penentuan harga optimal tiket masuk kawasan wisata alam Bantimurung
Penentuan harga optimal tiket masuk dilakukan dengan simulasi harga tiket masuk kawasan wisata alam Bantimurung. Simulasi dilakukan dengan memasukkan harga tiket masuk pada persamaan permintaan wisata sehingga persamaan per-mintaan wisata menjadi:
Y = β + β (X + TM) (6)0 1 1
Keterangan: Y = jumlah pengunjung per 1.000 penduduk β = intersep 0
β = koefisien regresi1
X = biaya perjalanan rata-rata (Rp)1
TM = harga tiket masuk
JPi
xJPxJSt
JSi1000
158Harga Optimal Tiket Masuk Wisata Alam Bantimurung, Wahyudi Isnan ..... ( )
Selanjutnya hasil perhitungan jumlah pengun-jung (Y) dan harga tiket masuk (TM) dimasukkan kedalam tabel simulasi sehingga didapatkan jumlah penerimaan yang merupakan hasil perkalian antara jumlah pengunjung dengan harga tiket masuk. Harga optimal tiket masukdidapatkan dengan membuat grafik antara jumlah penerimaan dan harga tiket masuk.
3. Kesediaan membayar pengunjung
Untuk menentukan total kesediaan membayar pengunjung pada berbagai harga tiket masuk digunakan persamaan sebagai berikut;
WTPi = Ti x A (7)
Keterangan:WTPi = kesediaan membayar dari pengunjung
pada harga tiket ke iTi = harga tiket masuk ke iA = jumlah penurunan pengunjung pada
harga tiket ke i
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pendugaan Persamaan PermintaanWisata Alam Bantimurung
Pendugaan persamaaan permintaan wisata alam Bantimurung dilakukan dengan membuat persamaan regresi antara jumlah pengunjung per 1.000 penduduk (Y) dengan biaya perjalanan rata-rata dari masing-masing daerah asal pengunjung (X1) beserta variabel sosial ekonomi lainnya. Hukum permintaan menyatakan bahwa jumlah barang yang diminta dalam suatu periode waktu tertentu berubah berlawanan dengan harganya, jika hal lain diasumsikan tetap (Samuelson & Nordhaus, 2009), sehingga semakin tinggi harganya semakin kecil jumlah barang yang diminta atau sebaliknya semakin rendah harganya maka semakin tinggi jumlah barang yang diminta (McEachern, 2001).
Distribusi jumlah pengunjung, rata-rata biaya perjalanan dan rata-rata pendapatan menurut zona ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Distribusi jumlah pengunjung dan rata-rata biaya perjalanan dari masing-masing zonaTable 1. Distribution of the number of visitors and average travel costs of each zone
No Zona (Zone)
Jumlah pengunjung
(Number of visitor) (orang)
Rata-rata total biaya perjalanan (Total average travel costs)
(Rp/orang)
Rata-rata total pendapatan (Total average income) (Rp/orang/tahun)
1 Makassar 34 54.319 28.041.180 2 Maros 31 28.403 18.207.096 3 Gowa 13 55.212 12.784.620 4 Takalar 11 60.877 24.981.816 5 Pangkep 8 53.313 23.328.000 6 Bone 3 157.333 23.199.996 7 Bulukumba 3 142.500 20.000.004 8 Barru 2 68.000 20.958.000 9 Bantaeng 2 87.500 17.400.000 10 Sinjai 2 190.250 9.300.000 11 Pare-pare 2 91.500 39.000.000 12 Tana Toraja 2 192.500 25.380.000 13 Sidrap 1 95.000 33.600.000 14 Pinrang 1 183.000 72.000.000 15 Enrekang 1 147.700 22.800.000 16 Palopo 1 262.000 18.000.000
Total(Total): 117 Rata-rata(Average): 116.838 Rata-rata (Average): 25.561.295 Rata-rata prosentase pendapatan untuk wisata (Average percentage of income for touring): 0,52%
Sumber (Source): Isnan, 2013.
zona Rp116.838 per orang.Tingginya biaya perjalanan dari zona Palopo tersebut dapat dimaklumi karena merupakan zona paling jauh dari kawasan wisata alam Bantimurung. Rata-rata per-sentase pendapatan pengunjung dari keseluruhan
Rata-rata biaya perjalanan (Tabel 1) dari masing-masing zona pengunjung ke kawasan wisata alam Bantimurung bervariasi mulai Rp28.403 (asal zona Maros) sampai dengan Rp262.000 (asal zona Palopo) dan rata-rata biaya perjalanan keseluruhan
159JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 155-163
transportasi
40%
konsumsi
21%
souvenir
9%
sewa
8%
lain
3%
Sumber (Source): Isnan, 2013.
Gambar 1. Distribusi biaya perjalanan menurut pengguna-annya, mencakupbiaya transportasi, konsumsi danbiayatiket masuk. Figure 1. Distributionof travelexpenses according to its use,study covers the cost of transportation, consumption and costof admission.
Tabel 2. Jumlah pengunjung per 1.000 penduduk untuk setiap zonaTable 2. The number of visitors per 1.000 inhabitants for each zon
No Zona (Zone)
Jumlah penduduk *) (Population)
(orang)
Sampel (Sample) Prediksi jumlah pengunjung dari zona
(Prediction of visitor number) (orang)
Pengunjung per 1.000 penduduk (Visitors per
1.000 inhabitants) (orang/tahun)
Orang %
1 Makassar 1.352.136 34 29,06 162.027 119,83 2 Maros 322.212 31 26,50 147.730 458,49 3 Gowa 659.512 13 11,11 61.951 93,94 4 Takalar 272.316 11 9,40 52.420 192,50 5 Pangkep 308.814 8 6,84 38.124 123,45 6 Bone 724.905 3 2,56 14.296 19,72 7 Bulukumba 398.531 3 2,56 14.296 35,87 8 Barru 167.653 2 1,71 9.531 56,85 9 Bantaeng 178.477 2 1,71 9.531 53,40 10 Sinjai 231.182 2 1,71 9.531 41,00 11 Pare-pare 130.563 2 1,71 9.531 73,00 12 Tana Toraja 223.306 2 1,71 9.531 42,68 13 Sidrap 274.648 1 0,85 4.766 17,35 14 Pinrang 354.652 1 0,85 4.766 13,44 15 Enrekang 192.163 1 0,85 4.766 24,80 16 Palopo 149.421 1 0,85 4.766 31,89
Jumlah(Total) 5.940.491 117 100 557.563**) Rata-rata (Average): 87,40
zona yang dikeluarkan untuk menikmati wisata alam Bantimurung sebesar 0,52%.Distribusi biaya perjalanan menurut penggunaannya, mencakup biaya transportasi, konsumsi, harga tiket masuk dan lain-lain dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1 menunjukkan bahwa proporsi terbesar biaya perjalanan yang dikeluarkan oleh pengunjung adalah untuk transportasi.Hal ini diduga karena pengunjung menggunakan kendaraan pribadi berupa mobil atau sepeda motor,
sehingga pengunjung mengeluarkan biaya bahan bakar minyak lebih besar daripada apabila menggunakan kendaraan umum.Keindahan kawasan wisata alam Bantimurung telah dikenal lama dan menarik wisatawan berkunjung. Pengunjung wisata alam Bantimurung berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.Berikut adalah daerah asal pengunjung dan hasil perhitungan jumlah pengunjung per 1.000 penduduk per tahun ditampilkan pada Tabel 2.
*) **)Sumber ( ): Sulawesi Selatan dalam angka, BPS, 2012; Data sekunder jumlah pengunjung tahun 2012Source
160Harga Optimal Tiket Masuk Wisata Alam Bantimurung, Wahyudi Isnan ..... ( )
Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat 16 zona asal pengunjung. Dari 16 zona tersebut, jumlah pengunjung per 1.000 penduduk terbesar berasal dari Kabupaten Maros sebanyak 458,49 sedangkan Kabupaten Pinrang merupakan kabupaten yang paling sedikit jumlah pengunjung per 1.000 penduduknya yaitu hanya 13,44. Sekalipun jumlah pengunjung dari Kota Makassar yang terbanyak yaitu 34 pengunjung, namun jumlah pengunjung per 1.000 penduduk tidak sebanyak dari Kabupaten Maros. Hal ini karena jumlah penduduk Kota Makassar adalah paling padat dibanding kabupaten lain di Sulawesi Selatan.
Berdasarkan hasil regresi dengan metode stepwisedengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 11.0 antara jumlah pengunjung per 1.000 penduduk dengan variabel-variabel sosial ekonomi pengun-jung, maka diperoleh persamaan terbaik per-mintaan wisata alam Bantimurung sebagai berikut:
Y = 200,539 – 0,001 X1
Dalam hal ini:Y = jumlah pengunjung per 1.000 pendudukX = total biaya perjalanan rata-rata (Rp/orang)1
Persamaan tersebut menjelaskan bahwa bila total biaya perjalanan rata-rata dari pengunjung sebesar Rp0, maka jumlah pengunjung per 1.000 penduduk adalah sebesar 200 orang. Setiap kenaikan biaya perjalanan rata-rata sebesar Rp1.000, akan menurunkan jumlah pengunjung per 1.000 penduduk sebanyaksatu orang.
B. Simulasi Harga Tiket Masuk Kawasan Wisata Alam Bantimurung
Simulasi harga tiket masuk dilakukan dengan kelipatan Rp15.000 mulai dari Rp0, hingga Rp180.000 yaitu pada saat jumlah pengunjung sama dengan 0. Hasil simulasi harga tiket masuk kawasan wisata alam Bantimurung ditampilkan pada Tabel 3.
Pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa dengan harga tiket masuk Rp0, maka diperoleh surplus konsumen sebesar Rp43.351.845.000 per tahun dan nilai kesediaan membayar sama dengan surplus konsumen yaitu Rp43.351.845.000 per tahun.Nilai rata-rata kesediaan membayar pengunjung adalah sebesar Rp73.106 per orang dan merupakan nilai rata-rata surplus konsumen yang diterima oleh pengunjung. Surplus konsumen tersebut dapat berupa uang atau kepuasan yang diperoleh pengunjung dalam menikmati kawasan wisata alam Bantimurung.
Kurva permintaan wisata alam Bantimurung pada berbagai harga tiket masuk disajikan pada Gambar 2.
Tabel 3. Simulasi harga tiket masuk wisata alam BantimurungTable 3. Simulation of the price of entrance tickets ecoturism of Bantimurung
Harga (Price)
Jumlah pengunjung (Number of
visitor)
Penerimaan (Revenue)
Penurunan ( decline)
Selisih WTP (WTP difference)
total WTP (WTP total)
Rata-rata WTP (WTP average)
Surplus konsumen
(Consumer surplus)
1 2 3 (1x2) 4 5 (1x4) 6 (6-5) 7 (6/2) 8 (6-3) 0 593.002 0 0 0 43.351.845.000 73.105,73 43.351.845.000
15.000 508.785 7.631.775.000 84.217 1.263.255.000 42.088.590.000 82.723,72 34.456.815.000 30.000 433.170 12.995.100.000 75.615 2.268.450.000 39.820.140.000 91.927,28 26.825.040.000 45.000 359.746 16.188.570.000 73.424 3.304.080.000 36.516.060.000 101.505,12 20.327.490.000 60.000 298.071 17.884.260.000 61.675 3.700.500.000 32.815.560.000 110.093,10 14.931.300.000 75.000 243.076 18.230.700.000 54.995 4.124.625.000 28.690.935.000 118.032,77 10.460.235.000 90.000 188.081 16.927.290.000 54.995 4.949.550.000 23.741.385.000 126.229,58 6.814.095.000
105.000 133.086 13.974.030.000 54.995 5.774.475.000 17.966.910.000 135.002,25 3.992.880.000 120.000 84.759 10.171.080.000 48.327 5.799.240.000 12.167.670.000 143.556,08 1.996.590.000 135.000 38.938 5.256.630.000 45.821 6.185.835.000 5.981.835.000 153.624,61 725.205.000 150.000 7.121 1.068.150.000 31.817 4.772.550.000 1.209.285.000 169.819,55 141.135.000 165.000 2.288 377.520.000 4.833 797.445.000 411.840.000 180.000 34.320.000 180.000 0 0 2.288 411.840.000 0 0
Total 43.351.845.000 164.056.950.000
Sumber (Source): Isnan, 2013.
161JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 155-163
Gambar 2. Kurva permintaan wisataalam BantimurungFigure 2. The demand curve ofBantimurungnaturalpark
Sumber ( ): Isnan (2013)Source
Gambar 2 menunjukkan bahwa pada harga tiket masuk sebesar Rp0 per orang maka jumlah pengunjung adalah sebanyak 593.002 orang, dan pada harga tiket masuk sebesar Rp180.000 per orang maka jumlah pengunjung adalah 0 orang. Pengunjung hanya bersedia membayar harga tiket masuk maksimal pada besaran harga Rp165.000 per orang. Pada harga tiket masuk sebesar Rp180.000 per orang maka sudah tidak ada pengunjung yang bersedia menikmati wisata alam di kawasan wisata alam Bantimurung. Pada harga tiket masuk Rp180.000 per orang pengunjung tidak mem-peroleh surplus konsumen dalam berwisata. Surplus konsumen merupakan perbedaan antara jumlah yang dibayarkan oleh pengguna untuk suatu produk dan kesediaan untuk membayar (Pomeroy, 1992 dalam Hayati, 2008). Sedangkan pada tingkat harga tiket masuk Rp0, pengunjung akan menikmati surplus konsumen sebesar daerah di bawah kurva permintaan atau sama dengan total kesediaan membayar dari pengunjung. Surplus pada harga Rp0 adalah surplus terbesar yang dapat dinikmati o leh pengunjung kawasan wisata a lam
Bantimurung. Surplus konsumen sebesar Rp43.351.845.000 per tahun yang dinikmati pengunjung terutama dinikmati oleh pengunjung yang berada lebih dekat dengan lokasi wisata alam Bantimurung. Sedangkan pengunjung yang berada jauh dari lokasi wisata alam Bantimurung akan menikmati lebih sedikit surplus konsumen.
Berdasarkan harga tiket masuk saat penelitian sebesar Rp15.000 maka pihak pengelola mem-peroleh penerimaan sebesar Rp7.631.775.000 per t a h u n , s u r p l u s k o n s u m e n s e b e s a r Rp34.456.815.000 per tahun dan nilai kesediaan membayar dari seluruh pengunjung sebesar Rp42.088.590.000 per tahun. Nilai rata-rata kesediaan membayar pengunjung adalah sebesar Rp82.724 per orang sehingga rata-rata pengunjung menikmati surplus konsumen sebesar Rp67.724 per orang.
Harga optimal tiket masukadalah harga tiket masuk yang mendatangkan penerimaan terbesar bagi pengelola. Harga optimal tiket masukkawasan wisata alam Bantimurung ditampilkan pada Gambar 3.
Sumber ( ): Isnan (2013)Source
Gambar3. Hubungan harga tiketmasuk dan pendapatanFigure 3. The relationship betweenprice of entranceticketand revenue
162Harga Optimal Tiket Masuk Wisata Alam Bantimurung, Wahyudi Isnan ..... ( )
Pada Gambar 3 terlihat bahwa harga optimal tiket masuk berada pada harga Rp75.000. Pada harga optimal tiket masuksebesar Rp75.000pihak pengelola wisata alam akan memperoleh penerimaan sebesar Rp18.230.700.000 per tahun. Penerimaan ini diperoleh pengelola dari penjualan tiket masuk kawasan wisata alam Bantimurung. Sedangkan nilai kesediaan membayar dari seluruh pengunjung adalah sebesar Rp28.690.935.000 per tahun dengan surplus konsumen Rp10.460.235.000 per tahun. Hasil penelitian Thur (2010) menunjuk-kan bahwa pengunjung kawasan lindung memiliki kesediaan membayar yang signifikan. Nilai kesediaan membayar rata-rata dari pengunjung wisata alam Bantimurung adalah sebesar Rp118.032 per orang, dan apabila harga tiket masuk sebesar Rp75.000, maka rata-rata pengunjung akan mendapatkan surplus konsumen sebesar Rp43.032 per orang.Pada kasus ini, jika yang diinginkan oleh pengelola wisata alam adalah kenaikan jumlah penerimaan, maka harga tiket masuk dapat dinaikkan dari Rp15.000 menjadi Rp75.000. Alpízar (2006) mendapatkan model yang menunjukkan bahwa harga untuk pengunjung dapat dinaikkan tergantung pada estimasi biaya marjinal. Harga tiket masuk sebesar Rp75.000 akan berakibat menurunnya jumlah pengunjung sebesar 52% namun tetap menguntungkan pengelola. Jumlah pengunjung yang berkurang dapat memberikan keuntungan bagi pengunjung karena mendapatkan ruang yang lebih banyak dalam menikmati wisata alam Bantimurung.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Pada harga tiket masuk saat penelitian sebesar Rp15.000, pengelola wisata alammemperoleh penerimaan sebesar Rp7.631.775.000 per tahun dan surplus konsumen sebesar Rp34.456.815.000 pertahun, maka nilai kesediaan membayar seluruh pengunjung sebesar Rp42.088.590.000 per tahun. Nilai rata-rata kesediaan membayar dari pengun-jung adalah sebesar Rp82.724 per orang sehingga rata-rata pengunjung menikmati surplus konsumen sebesar Rp67.724 per orang.
Harga optimal tiket masuk adalah Rp75.000 dan memberikan penerimaan bagi pengelola sebesar Rp18.230.700.000 per tahun, nilai kesediaan
membayar seluruh pengunjung Rp28.690.935.000 per tahun, dan surplus konsumen sebesar Rp10.460.235.000 per tahun. Nilai kesediaan membayar rata-rata dari pengunjung sebesar Rp118.032 per orang sehingga rata-rata pengunjung mendapatkan surplus konsumen sebesar Rp43.032 per orang.
Kenaikan harga tiket masuk dapat menguntung-kan pengelola dan pengunjung, yaitu penerimaan optimal bagi pengelola dan ruang yang lebih luas bagi pengunjung dalam menikmati wisata alam Bantimurung.
B. Saran
Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor wisata khususnya wisata alam Bantimurung, disarankan pengelola kawasan wisata alam Bantimurung untuk menaikkan harga tiket masuk. Besaran kenaikan harga tiket masuk kawasan wisata alam Bantimurung adalah harga optimal yang mendatangkan penerimaan terbesar bagi pengelola yaitu sebesar Rp75.000.
UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)
Penulis mengucapkan terima kasih kepada stafBalai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang telah membantu pengambilan data selama penelitian serta dewan redaksi dan editor yang telah membantu menyempurnakan naskah ini.
DAFTAR PUSTAKA
Alpízar, F. (2006). The pricing of protected areas in nature-based tourism: A local perspective. Ecological Economics, 56(2), 294-307. http://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2005.02.005.
Badan Pusat Statistik. (2012). Sulawesi dalam angka. Makassar: Badan Pusat Statistik.
Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. (2012). Laporan tahunan tahun 2011. Maros: Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.
163JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 155-163
Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. (2013). Laporan tahunan tahun 2012. Maros: Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.
Brey, R., Riera, P., & Mogas, J. (2007). Estimation of forest values using choice modeling: An application to Spanish forests. Ecological Economics, 64(2), 305-312. http://doi.org/ 10.1016/j.ecolecon.2007.07.006.
Cordell, H. K., Betz, C. ., & Green, G. . (2002). Recreation and the environmental as cultural dimensions in contemporary American society. Leisure Science, 24, 13-41.
Davis, L. S., & Johnson, N. K. (1987). Forest Management (3rd ed.). New York:Mc.Graw-Hill Book Company.
Douglass, R. (1982). Forest recreation (3rd ed.). New York: Pergamon Press.
Ginoga, K. L., & Lugina, M. (2007). Metode umum kuantifikasi nilai ekonomi sumber daya hutan. Info Sosial Ekonomi, 7(1), 17-27.
Hayati, N. (2008). Valuasi ekonomi wisata Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada.
Isnan, W. (2013). Elastisitas permintaan jasa wisata alam bantimurung.. Makasar: Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin.
Karyono, O. K., & Muttaqin, M. Z. (2003). Dampak penetapan tarif pungutan masuk terhadap tingkat kunjungan dan pendapatan hutan
wisata. Studi kasus di Karangnini Ciamis Jawa Barat. Jurnal Ilmiah Kesatuan, 5(2), 31-38.
McEachern, W. (2001). Ekonomi mikro: Pendekatan kontemporer. Jakarta: Salemba Empat.
Nuva, R., Shamsudin, M. N., Radam, A., & Shuib, A. (2009). Willingness to pay towards the conservation of ecotourism resources at Gunung Gede Pangrango National Park, West Java, Indonesia. Journal of Sustainable Development, 2(2), 173-186. http://doi.org/ 10.5539/jsd.v2n2P173.
Samuelson, P., & Nordhaus, W. (2009). Economics (19th ed.). New York: Mc Graw-Hill.
Sevilla, C. G., Ochave, J. A., Punsalan, T. G., Regala, B. P., & Uriarte, G. B. (2006). Pengantar metode penelitian. Jakarta: UI Press.
Sudarmalik. (1995). Studi nilai manfaat rekreasi dan prospek pengembangan di Taman Wisata Alam Bantimurung Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Bogor: Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
Thur, S. M. (2010). User fees as sustainable financing mechanisms for marine protected areas: An application to the Bonaire National Marine Park. Marine Policy, 34(2010), 63-69. http://doi.org/10.1016/j.marpol.2009.04.008.
Utami, A. S., & Hardiyansyah, G. (2012). Studi permintaan konsumen terhadap manfaat rekreasi alam di obyek wisata Pantai Sinka Island Park Kelurahan Sedau Kota Singkawang. Jurnal Eksos, 8, 73-79.
165
SINERGI TATA RUANG TERHADAP PELAKSANAAN REDD+: STUDI KASUS DI KABUPATEN KATINGAN, KALIMANTAN TENGAH
(Synergy of Spatial Planning for REDD+ Implementation at Katingan District, Central Kalimantan)
Nugroho Adi Utomo & Santun R. P. Sitorus1 2
1 Pascasarjana IPB, Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Fakultas Pertanian, Wing 18 Level 6, Jalan Meranti
Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680, Indonesia.
E-mail : [email protected] Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, Fakultas Pertanian, Wing 18 Level 6, Jalan Meranti Kampus
IPB Darmaga, Bogor 16680, Indonesia.
E-mail: [email protected]
Diterima 2 Februari 2016, direvisi 16 Februari 2016, disetujui 21 November 2016
ABSTRACT
One effort to mitigate climate change is by perform the REDD+, which are containing emission reduction activities from deforestation and land degradation, sustainable forest management, carbon stock enhancement, and forest conservation. Katingan District is located in the REDD+ Pilot Project Province, Central Kalimantan. This study aims to analyze pattern of changes in the use of forest land, inconsistency of existing land use, content of policies concerning of basic element and process of REDD+, preferences of stakeholder to emerging REDD+ initiatives, and to formulate improvement of RTRW. The study was using Analyses of change and inconsistencies land use, Analytical Hierarchy Process, and descriptive analyses. The result of the study was forest land use was 60.47% and change patterns of forest land use occurred from forest to shrub/open land turned into plantation, agriculture and settlement. Analyses of inconsistencies land use indicated small value of inconsistency. While basic element and process of REDD+ contained in regional planning document; and stakeholders interested in the REDD+ initiative for direct benefit. Therefore, REDD+ initiatives possible to be implemented with some improvements in RTRW, through synchronization of REDD+ initiatives, and space allocation for REDD+ initiatives should be placed in protected areas and partially in cultivated areas.
Keywords: Land use; spatial planning; stakeholder preferences; REDD+; Katingan.
ABSTRAK
Salah satu upaya mitigasi perubahan iklim adalah REDD+, yang mencakup penurunan emisi melalui upaya penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan cadangan karbon hutan, serta upaya konservasi hutan. Kabupaten Katingan terletak di wilayah Provinsi Pilot Percontohan REDD+, Kalimantan Tengah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola perubahan penggunaan lahan hutan, inkonsistensi penggunaan lahan, isi kebijakan perencanaan daerah dengan elemen dasar dan proses REDD+, pendapat stakeholder atas inisiatif REDD+, dan merumuskan arahan RTRW. Metode analisis yang digunakan adalah analisis perubahan dan inkonsistensi penggunaan lahan, analisis isi, Analisis Proses Bertingkat ( ), serta analisis Analytical Hierarchy Processdeskriptif. Hasilnya adalah penggunaan lahan hutan mencapai 60,47% dan pola perubahan penggunaan lahan hutan terjadi dari hutan menjadi semak belukar/tanah terbuka kemudian menjadi tanaman perkebunan, pertanian dan pemukiman. Analisis inkonsistensi menunjukkan tingkat inkonsistensi kecil. Sementara itu elemen dasar dan proses REDD+ terkandung di dalam dokumen perencanaan daerah; dan tertarik akan inisiatif REDD+ untuk stakeholder memperoleh manfaat langsung. Inisiatif REDD+ dapat berjalan di Kabupaten Katingan dengan penyempurnaan RTRW, melalui upaya sinkronisasi inisiatif REDD+ dan RTRW Kabupaten serta upaya akomodasi ruang inisiatif REDD+ pada kawasan lindung dan sebagian kawasan budi daya.
Kata kunci: Penggunaan lahan; penataan ruang; preferensi ; REDD+; Katingan.stakeholder
JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 165-176
166
Hutan Kayu – Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) seluas 108.255 ha yang dilaksanakan oleh P.T. Rimba Makmur Utama (PT. RMU). Disamping itu inisiatif REDD+ lainnya dikuatkan melalui SK Nomor 6315/Menhut-VII//IPSDH/2012 (Surat Keputusan Menteri Kehutanan, 2012a) tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) dalam kawasan hutan (Revisi III). Kawasan hutan dalam area PIPPIB ini sering diistilahkan dengan kawasan moratorium.
Kabupaten Katingan merupakan kabupaten baru yang mengalami pemekaran sejak tahun 2002, melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002. Luas wilayahnya mencapai 2.040.300 ha, sekitar 11,59 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Persentase luasan hutan di Kabupaten Katingan pada tahun 2006 mencapai 69,4% (Niin, 2010). Disamping itu sektor (lapangan usaha) pertanian masih merupakan sektor yang dominan dan menjadi andalan dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Katingan dibandingkan sektor-sektor yang lain. Inisiatif REDD+ di Kabupaten Katingan akan menghadapi kendala terkait dengan kondisinya sebagai kabupaten pemekaran. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, secara PDRB, sub-sektor perkebunan, peternakan dan pertanian menunjukkan tren perkembangan positif, sementara sub-sektor kehutanan menurun sejak tahun 2005 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, 2010). Pada tahun 2005 luas areal pertanian (padi), kebun karet dan sawit berturut-turut adalah 12.121 ha, 13.292 ha dan 625 ha (Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, 2010). Sementara pada tahun 2011, luas areal pertanian (padi), kebun karet dan sawit berturut-turut adalah 18.013 ha, 20.947 ha dan 98.069 ha (Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, 2012). Pertam-bahan luasan lahan kebun dan pertanian ini memunculkan kekhawatiran akan adanya ekspansi yang tidak terkendali dan pada akhirnya memengaruhi kawasan hutan. Belum lagi permasalahan belum tuntasnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Katingan sampai saat ini semakin menambah ketidakpastian inisiatif REDD+ bisa berjalan lancar di tingkat kabupaten. Penelitian ini menjadi penting mengingat RTRW Katingan merupakan kebijakan payung dalam penataan ruang di tingkat Kabupaten dan inisiatif REDD+ diharapkan bisa bersinergi dengan RTRW.
I. PENDAHULUAN
Dunia saat ini sedang dilanda pemanasan global ( ) yang ditunjukkan dengan mening-global warmingkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Emisi GRK ini diakibatkan oleh semakin berkembangnya industri di negara maju dan juga maraknya pembalakan hutan maupun kebakaran hutan di negara berkembang yang pada akhirnya menyebab-kan perubahan iklim. Fenomena perubahan iklim ini dihadapi dunia melalui adaptasi (upaya untuk menyesuaikan dengan perubahan iklim dan lingkungan) dan mitigasi (upaya untuk menurunkan emisi GRK). Salah satu upaya mitigasi perubahan iklim yang kemudian digagas oleh banyak pihak adalah melalui pendekatan REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation plus), yang mencakup penurunan emisi melalui upaya penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan cadangan karbon hutan, serta upaya konservasi hutan (Angelsen, Brockhaus, Sunderlin, & Verchot, 2013). Secara umum deforestasi dunia menyumbang hingga 18% emisi GRK, atau sekitar 5,8 triliun ton CO ekuivalen tiap tahunnya (Angelsen ., 2009). et al2
Upaya untuk menurunkan emisi GRK melalui penurunan deforestasi merupakan salah satu kesempatan besar dengan biaya yang efektif dan berdampak cepat pada turunnya emisi GRK (Stern, 2006).
Pada saat ini ada beberapa proyek pilot yang sudah dilakukan dan Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu Provinsi Pilot Proyek REDD+. Tidak hanya tingkat Provinsi Kalimantan Tengah saja yang melakukan persiapan dalam program REDD+ ini, tetapi tingkat kabupaten pun turut mempersiapkannya, salah satunya adalah Kabupaten Katingan. Pemerintah Kabupaten Katingan sendiri, sejak Desember 2011 melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Katingan Nomor 660/302/KPTS/XII/2011 telah mem-bentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengurangan Emisi dari Kegiatan Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) Kabupaten Katingan (Surat Keputusan Bupatei Katingan, 2011). Pokja REDD+ Katingan saat ini masih membuat draft Rencana Strategi dan Aksi terkait pengurangan emisi dan kegiatan REDD+. Salah satu Inisiatif REDD+ di Kabupaten Katingan yang sedang berjalan adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Sinergi Tata Ruang terhadap Pelaksanaan REDD+: ..... (Nugroho Adi Utomo & R.P. Sitorus)
B. Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dan hasil pengisian kuesioner oleh responden yang merupakan stakeholder yang terlibat dalam proses inisiatif REDD+. Pertanyaan wawancara ditujukan untuk mengetahui sejauh mana upaya, kebijakan, kelembagaan serta harapan masing-masing terkait REDD+ di stakeholderKabupaten Katingan. Pertanyaan untuk kuesioner meliputi pertanyaan tentang preferensi dan persepsi para pihak terhadap keberlanjutan REDD+. Sebanyak 22 responden dipilih dalam analisis preferensi para pihak yang meliputi pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPRD, swasta dan tokoh masyarakat dengan prinsip bahwa responden yang dipilih mempunyai pemahaman tentang pembangunan di Kabupaten Katingan dan terlibat aktif dalam inisiatif REDD+.
Data sekunder berupa Citra Landsat 7 ETM+ tahun 2000, 2006 dan 2012, peta tematik, dokumen kebijakan perencanaan daerah, dan data statistik daerah.
Penelitian ini bertujuan: (1) Menganalisis pola perubahan penggunaan lahan hutan menjadi penggunaan lain di Kabupaten Katingan; (2) Menganalisis konsistensi penggunaan lahan eksisting dengan pengalokasian ruang pada RTRW; (3) Menganalisis isi kebijakan tata ruang yang mendukung inisiatif REDD+; (4) Menganalisis pendapat atas munculnya inisiatif stakeholder REDD+; (5) Merumuskan arahan penyempurnaan RTRW Katingan.
II. METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2012–Juni 2013. Penelitian lapang dilakukan di wilayah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah mulai bulan Januari–Maret 2013, khususnya di 4 (empat) desa dan 2 (dua) kecamatan di sekitar areal konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) PT. RMU (Gambar 1a). Desa Baun Bango dan Desa Muara Bulan (Kecamatan Kamipang) serta Desa Galinggang dan Desa Tewang Kampung (Kecamatan Mendawai).
167JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 165-176
Sumber (Source): Peta Administrasi Kabupaten Katingan; Peta Moratorium Kawasan Hutan Revisi III; Peta Rencana Konsesi IUPHHK-RE PT. Rimba Makmur Utama, 2013
Gambar 1. Peta Kabupaten Katingan a) Administrasi & inisiatif REDD+ dan b) Penggunaan Lahan Tahun 2012
Figure 1. Map of Katingan District a) Administration and REDD+ initiatives; and b) Land Use of 2012
C. Analisis Data
Penelitian ini menggunakan lima metode analisis data yaitu: Analisis perubahan penggunaan lahan, analisis inkonsistensi penggunaan lahan, analisis konten, Analisis Proses Bertingkat (Analytical Hierarchy Process), dan analisis deskriptif.
1) Analisis perubahan penggunaan lahan
Analisis perubahan penggunaan lahan merupa-kan analisis dengan memanfaatkan salah satu aplikasi umum dalam pemanfaatan data citra satelit (penginderaan jauh) dalam memantau perubahan. Tahapan yang digunakan meliputi persiapan citra, klasifikasi citra, interpretasi citra dan pembuatan peta penggunaan lahan.
Analisis deteksi perubahan penggunaan lahan tahun 2000, 2006 dan 2012 dilakukan setelah diperoleh peta penggunaan lahan pada masing-masing tahun tersebut dengan cara membuat matriks transformasi yang dapat mendeteksi perubahan penggunaan lahan ke perubahan lainnya termasuk luas dan sebarannya.
2) Analisis inkonsistensi penggunaan lahan
Analisis ini dilakukan pada dua jenis peta berbeda yang ditumpang-tindihkan (overlay) untuk melihat seberapa jauh tingkat konsistensi dan
inkonsistensi pemanfaatan ruang terhadap RTRW dan kawasan hutan.
3) Analisis isi
Analisis isi (content analysis) secara sederhana diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah “teks” (Ekomadyo, 2006). Langkah-langkah kegiatan dalam metode analisis isi (Ekomadyo, 2006) adalah (1) menentukan unit analisis (misalnya jumlah teks yang ditetapkan sebagai kode), (2) menentukan sampling, (3) menentukan variabel, (4) menyusun kategori pengkodean, dan (5) menarik kesimpulan (Tabel 1).
Dalam penelitian ini variabel yang digunakan untuk menganalisis isi adalah melalui prinsip-prinsip REDD+ menurut Stern (2008) dan Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ (2012). Ada beberapa elemen penting berupa prinsip-prinsip agar program mitigasi perubahan iklim, seperti REDD+ optimal, yaitu: efektifitas, efisiensi dan kesetaraan. Efektif berarti dapat menurunkan emisi karbon dengan tingkat resiko dari perubahan iklim yang wajar; Efisiensi berarti dapat diimplementasi-kan dengan menggunakan biaya yang efektif; Kesetaraan berarti harus ada peran masing-masing dari setiap negara-negara yang maju, berkembang maupun yang miskin sekalipun Stern (2008).
168
Sumber (Source): Modifikasi dari Yuris, 2009
Pertanyaan penelitian
(Research question)
Sumber data terpilih
(Data source)
Kategori analisis (Category of analysis)
Pengkodean (Coding)
Skala/item berdasarkan kriteria tertentu
(Nominal scale based on defined criteria)
Apakah ada pesan/isi yang berkaitan dengan elemen dasar dan proses REDD+ Katingan?
Dokumen perencanaan di Kabupaten Katingan yaitu : 1. RPJPD
Kabupaten Katingan Tahun 2005 – 2025
2. Draft RTRW Kabupaten Katingan Tahun 2011 – 2031
Elemen dasar dan proses REDD+ di Indonesia meliputi 3 (tiga) elemen :
Skala n omina l Apabila terdapat elemen dasar dan proses REDD+ di Indonesia dalam teks maka diberi nilai “1”; dan apabila tidak terdapat elemen dasar dan proses REDD+ dalam teks maka diberi nilai“0”.
1. Elemen reduksi emisi; Kode 1; a. Perubahan Iklim • Kode 1a b. Pelestarian hutan • Kode 1b
2. Elemen manfaat tambahan (Co-benefit) ;
Kode 2;
a. Kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati
• Kode 2a
b. Peningkatan kesejahteraan • Kode 2b 3. Elemen Ekuitas; Kode 3
a. Keadilan gender • Kode 3a b. Hak publik • Kode 3b c. Transparansi dan partisipasi • Kode 3c d. Akuntabel • Kode 3d
Tabel 1. Tahapan analisis isi elemen dasar dan proses REDD+ dalam dokumen perencanaan daerahTable 1. Step of content analysis of REDD+ process in the regional planning documents
Sinergi Tata Ruang terhadap Pelaksanaan REDD+: ..... (Nugroho Adi Utomo & R.P. Sitorus)
169
Implementasi REDD+ di Indonesia dilandas-kan atas lima prinsip: efektif, efisien, adil, transparan, dan akuntabel, yang dijabarkan sebagai berikut: (1) Efektif: menurunkan emisi dan menghasilkan manfaat tambahan; (2) Efisien: mendatangkan keuntungan finansial, ekologis, dan sosial secara optimal. (3) Adil: kesetaraan bagi semua orang; (4) Transparan: memberi pemahaman yang utuh dan kesempatan kepada semua pihak; (5) Akuntabel: pelaksanaan REDD+ dapat diper-tanggungjawabkan. Dengan demikian elemen dasar REDD+ itu sendiri meliputi pencapaian upaya perubahan iklim dan juga pencapaian upaya memperoleh manfaat tambahan. Elemen dasar REDD+ ini kemudian di dalam pelaksanaannya juga perlu mengacu pada elemen proses yang meliputi keadilan (hak publik dan gender), transparansi dan akuntabel (Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ Indonesia, 2012). Atas dasar inilah kemudian disusun variabel untuk memudahkan proses analisis isi, lihat Tabel 1.
4) Proses analisis bertingkat (Analytical Hierarchy Process, AHP)
Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, strategik dan dinamik menjadi bagian-bagiannya, serta menata dalam suatu hierarki (Marimin, 2004). Kemudian tingkat kepentingan setiap variabel diberikan nilai numerik secara subjektif tentang arti penting variabel tersebut secara relatif dibanding-
kan dengan variabel yang lain. Dari berbagai pertimbangan tersebut kemudian dilakukan analisis untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas ter tinggi dan berperan untuk memengaruhi hasil pada sistem tersebut.
Parnphumeesup & Kerr (2011) dalam peneli-tiannya terkait mekanisme pembangunan bersih melakukan pendekatan AHP untuk menilai preferensi stakeholder melalui aspek manfaat (penghasilan tambahan, lapangan kerja, reduksi emisi CO , menurunnya pembakaran residu 2
biomassa) dan aspek biaya sosial (debu, kebisingan, dan pencemaran). Sementara menurut Angelsen et al. (2013), REDD+ juga mem-perhatikan sejumlah isu lama dan baru yang kesemuanya menunjuk pada perlunya perubahan dalam kebijakan-kebijakan dan praktik bisnis seperti biasa untuk dapat mewujudkan potensi REDD+, contohnya adalah: i) hak adat dan masyarakat, serta konflik tentang penggunaan hutan oleh kelompok lokal dan perusahaan kehutanan komersial berskala besar, ii) tata kelola, korupsi dan ekonomi politis dalam pemanfaatan hutan; iii) biaya yang tidak efisien dan beranggaran tinggi atas berbagai kebijakan dan praktik mendukung kegiatan yang menghancurkan hutan. Penulis membuat formulasi keberlanjutan inisiatif REDD+ ke dalam 2 (dua) bagian utama (manfaat REDD+ dan biaya sosial) yang meliputi 3 (tiga) aspek diantaranya (langsung dan tidak langsung serta pertimbangan sosial) seperti tergambar dalam Gambar 2.
JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 165-176
Keberlanjutan Inisiatif REDD+ di Katingan
Manfaat REDD+
Biaya Sosial
Langsung
Tidak Langsung
Pertimbangan Sosial
Ta
mbahan
Penghasila
n
Berku-rangnyaBencana
Alam
Lapangan Pekerjaan
RehabilitasiHutan
Keterse-diaan AirTanah
Hasil Hutan Non Kayu
Konflik antar
Pemerintah
Konflik Pemerintah-
Masyarakat
Konflik antar
Masyarakat
Sumber ( ): Data diolah ( ), 2013Source Data processed
Gambar 2. Struktur hirarki preferensi keberlanjutan REDD+ dengan AHP Figure 2. Hierarchy structure for preference of REDD+ continuation using AHP
170
5) Analisis deskriptif
Analisis deskriptif bertujuan menganalisis arahan penyempurnaan RTRW secara kualitatif didasarkan pada beberapa hasil dari analisis sebelumnya dalam penelitian ini.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kabupaten Katingan
Kabupaten Katingan terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, ibukotanya di Kasongan, dengan koordinat geografis antara 0º20'-3º38' Lintang Selatan dan 112º00'-113º45' Bujur Timur. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Malawi Provinsi Kalimantan Barat; sebelah timur dengan Kabupaten Gunung Mas, Kota Palang-karaya, dan Kabupaten Pulang Pisau; sebelah selatan dengan Laut Jawa; sedangkan sebelah barat dengan Kabupaten Kotawaringin Timur serta Kabupaten Seruyan.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan setelah pemekaran selalu positif dengan kecen-derungan terus meningkat. Pertumbuhan positif ini pun disertai dengan bertambah besarnya area untuk sektor perkebunan, pertanian dan pertambangan. Dalam Tabel 2, luasan lahan yang digunakan untuk sektor pertanian, perkebunan dan pertambangan semakin meningkat dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. Dari sisi pengembangan inisiatif REDD+, secara kelem-bagaan saat ini ada Kelompok Kerja REDD+ (Pokja REDD+) yang saat ini masih dalam tahap merencanakan kegiatan terkait perubahan iklim di Kabupaten Katingan. Sudah ada 1 (satu) perusahaan, IUPHHK-RE PT. RMU, yang mengembangkan restorasi ekosistem yang sudah mulai menjalankan beberapa kegiatan pendahuluan.
B. Pola Perubahan Penggunaan Lahan Hutan di Kabupaten Katingan
Analisis perubahan penggunaan lahan dilakukan dengan tahapan interpretasi citra satelit pada 3 (tiga) titik tahun, yaitu tahun 2000, 2006 dan 2012. Pertimbangan pemilihan tahun didasarkan atas sebelum pemekaran kabupaten (tahun 2000), setelah pemekaran kabupaten (tahun 2006) dan setelah implementasi inisiatif REDD+ melalui moratorium hutan (tahun 2012). Klasifikasi penggunaan lahan pada penelitian ini mengguna-kan acuan pembagian kelas penggunaan dan penutupan lahan yang dikeluarkan oleh Badan Planologi Kehutanan yang kemudian digeneralisasi menjadi 5 (lima) kelas penggunaan lahan dan 1 (satu) kelas tutupan lahan. Lima kelas penggunaan lahan di Kabupaten Katingan meliputi hutan, tanaman tahunan (perkebunan), pertanian pangan lahan kering, pemukiman, dan semak belukar/ tanah terbuka serta 1 (satu) tutupan lahan berupa tubuh air (meliputi wilayah perairan seperti sungai, rawa, danau, dan wilayah yang tergenang air).
Interpretasi citra Landsat pada 3 (tiga) titik tahun, di Kabupaten Katingan dengan mengguna-kan kombinasi antara klasifikasi terbimbing (supervised classification) dan manual/visual, menghasilkan peta sebaran penggunaan lahan pada tahun 2000, 2006 dan tahun 2012 seperti tertera pada Tabel 3. Sejak tahun 2000 hingga 2012 terjadi penurunan luas tutupan hutan, dimana saat ini luasnya 1.242.554 ha (sekitar 65% dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Katingan). Kecen-derungan kelas penggunaan lahan pemukiman, pertanian pangan lahan kering dan tanaman tahunan cenderung positif, artinya terjadi peningkatan baik di tahun 2006 dan juga 2012. Begitu pula dengan kelas penggunaan lahan semak belukar/tanah terbuka yang terus bertambah luas
Sinergi Tata Ruang terhadap Pelaksanaan REDD+: ..... (Nugroho Adi Utomo & R.P. Sitorus)
Komoditas (Products)
Luas (ha) (Area) (ha)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kelapa sawit 156 625 625 694 1.540 35.422 79.719 98.069 Karet 9.198 13.292 13.266 14.740 15.419 - - 20.947
Pertanian 8.245 12.121 12.121 15.183 16.184 16.375 20.915 18.013 Pertambangan - - - - - - - 21.579
- = tidak ada data Sumber (Source): Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, 2010; Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, 2012; Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Katingan, 2012.
Tabel 2. Luas areal perkebunan, pertanian (padi), dan pertambangan 2004-2011 di Kabupaten KatinganTable 2. Area of plantations, agriculture (rice), and mining from 2004 to 2011 in Katingan District
171
dengan kemungkinan sebagian akan bisa berubah menjadi kawasan pemukiman, pertanian dan perkebunan seiring dengan semakin berkembang-nya pembangunan di Kabupaten Katingan di masa mendatang.
Berdasarkan struktur penggunaan lahan, luasan penggunaan lahan di Katingan tidak mengalami perubahan yang berarti, meskipun ada kecen-derungan pengembangan wilayah untuk aktivitas tanaman tahunan (perkebunan) dan pertanian pangan lahan kering serta perluasan area pemu-kiman pada periode 2000-2012. Kecenderungan berkurangnya luasan lahan hutan juga meng-
indikasikan adanya perubahan hutan untuk pengembangan wilayah. Pola perubahan lahan hutan menjadi penggunaan lahan lainnya diperoleh berdasarkan overlay antara peta penggunaan lahan tahun 2000, 2006 dan 2012, seperti tertera pada Gambar 3. Sepanjang tahun 2000 hingga 2012, berdasarkan analisis citra, tutupan hutan 2012 (dibandingkan dengan tutupan hutan 2000) berkurang 17,7%, yang terkonversi menjadi berubah menjadi pemukiman (0,1%), pertanian (0,8%), perkebunan (1,9%) dan sebagian besar semak belukar/tanah terbuka (14,9%).
JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 165-176
Penggunaan lahan/ha (Land use/ha)
Hutan (Forest)
Pemu-kiman
(Settlement)
Pertanian pangan
lahan kering (Dryland agriculture
food)
Tanaman tahunan (Perennial
crops)
Semak belukar/ tanah terbuka
(Shrubs/Clearing)
Tubuh air
(Water body)
Jumlah (Total)
Tahun 2000 Luas 1.508.489 2.871 31.077 1.736 489.778 20.735 2.054.686
% 73,42 0,14 1,51 0,08 23,84 1,01 100
Tahun 2006 Luas 1.346.795 5.496 47.909 23.455 610.296 20.735 2.054.686
% 65,55 0,27 2,33 1,14 29,70 1,01 100
Tahun 2012 Luas 1.242.554 7.843 65.489 63.977 654.088 20.735 2.054.686
% 60,47 0,38 3,19 3,11 31,83 1,01 100 Perubahan
Tahun 2000 - 2006
Luas -161.695 2.625 16.832 21.719 120.518 0 %* -10,72 91,45 54,16 1.251,33 24,61 0,00
Perubahan Tahun 2006 -
2012
Luas -104.241 2.347 17.580 40.522 43.792 0 %* -7,74 42,71 36,70 172,76 7,18 0,00
Perubahan Tahun 2000 -
2012
Luas -265.936 4.973 34.412 62.241 164.310 0 %*
-17,63
173,21
110,73
3.585,92
33,55
0,00
Sumber (Source): Data diolah (Data processed), 2013
PEMUKIMAN
SEMAK BELUKAR/ TANAH TERBUKA
HUTAN
PERTANIAN PANGAN
LAHAN KERING
TANAMAN TAHUNAN/
PERKEBUNAN
82,3%
14,9%
0,8%
1,9%
0,1%
Tabel 3. Penggunaan Lahan Kabupaten Katingan Tahun 2000, 2006 dan 2012 Table 3. L and Use of Katingan District Year of 2000, 2006 and 2012
Sumber ( ): Data diolah ( ), 2013Source Data processed
Gambar 3. Pola transisi perubahan penggunaan lahan (2000 – 2012) di Kabupaten Katingan Figure 3. Transition pattern of land use change (2000 – 2012) at Katingan District
172
C. Inkonsistensi RTRW Katingan dan Kawasan Hutan dengan Penggunaan Lahan
Dari hasil analisis inkonsistensi, overlay antara peta jenis penggunaan lahan dan peta rencana pola ruang RTRW Kabupaten Katingan, ternyata jumlah luasan penggunaan lahan yang inkonsisten terhadap RTRW relatif kecil, hanya 0,45% dari luasan kabupaten saja (sekitar 7.983 ha). Hasil rincian yang menunjukkan inkonsistensi peng-gunaan lahan dengan RTRW Katingan diantaranya:1. Jenis penggunaan lahan pemukiman, yang
berada pada kawasan hutan produksi (1.833 ha), dan kawasan hutan produksi terbatas (90 ha).
2. Jenis penggunaan lahan pertanian pangan lahan kering, yang berada pada kawasan hutan produksi (24.617 ha) dan kawasan hutan produksi terbatas (343 ha).
3. Jenis penggunaan lahan tanaman tahunan/ perkebunan, yang berada pada kawasan hutan produksi (31.088 ha) dan kawasan hutan produksi terbatas (722 ha).Hal ini menunjukkan adanya penggunaan lahan
yang tidak sesuai dengan RTRW kabupaten khususnya arahan rencana pola ruang RTRW. Fenomena seperti ini juga bisa mengindikasikan kemungkinan yang disebabkan lemahnya meka-nisme kontrol oleh pemerintah daerah serta lemahnya penegakan hukum.
Data kawasan hutan yang digunakan dalam analisis ini adalah data kawasan hutan terbaru yang dirilis Kementerian Kehutanan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor SK. 529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/ KPTS/UM/10/1982 tentang penunjukan areal hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah (Surat Keputusan Menteri Kehutanan, 2012b). Hasilnya menunjukkan ada inkonsistensi penggunaan lahan eksisting dengan kawasan hutan, yaitu:1. Jenis penggunaan lahan pemukiman, yang
berada pada kawasan hutan produksi (661 ha) dan kawasan hutan produksi terbatas (120 ha).
2. Jenis penggunaan lahan pertanian pangan lahan kering, yang berada pada kawasan hutan produksi (3.697 ha) dan kawasan hutan produksi terbatas (4.701 ha).
3. Jenis penggunaan lahan tanaman tahunan/ perkebunan, yang berada pada kawasan hutan produksi dengan luas mencapai 26.317 ha.
Secara agregat, luas total lahan yang inkonsisten terhadap kawasan hutan dalam berbagai jenis penggunaan relatif kecil yaitu sekitar 2% dari luasan kabupaten (sekitar 35.496 ha). Hal ini menunjukkan adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kawasan hutan khususnya kawasan hutan menurut SK Menteri Kehutanan Nomor SK. 529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/ UM/ 10/1982 tentang penunjukan areal hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah (Surat Keputusan Menteri Kehutanan, 2012b).
D. Elemen Dasar dan Proses REDD+ dalam Dokumen Perencanaan Wilayah
Pada bagian ini, akan dibahas adanya substansi elemen dasar dan proses REDD+ yang terkandung dalam dua dokumen perencanaan daerah di Kabupaten Katingan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan tahun 2005–2025 dan draft RTRW Kabupaten Katingan tahun 2011–2031. Dua dokumen tersebut memiliki jangka waktu yang sama panjangnya, yaitu 20 tahun, sehingga setidaknya juga akan sejalan dengan inisiatif REDD+ yang juga berorientasi pada jangka panjang.
1) Elemen dasar dan proses REDD+ dalam RPJPD Katingan 2005 – 2025
Hasil interpretasi analisis isi RPJPD Kabupaten Katingan 2005–2025 ini ditentukan berdasarkan persentase kumulatif pada setiap faktor penting atas 3 (tiga) elemen dasar dan proses REDD+ (reduksi emisi, manfaat tambahan dan ekuitas) secara menyeluruh yang terkandung didalam dokumen RPJPD. Hasil interpretasinya dapat dilihat pada Tabel 4. Dalam setiap elemen dasar dan proses REDD+, dapat dilihat faktor yang paling banyak kandungannya adalah faktor peningkatan kesejahteraan (dalam elemen manfaat tambahan), hingga 33,33 %. Kemudian faktor transparansi dan partisipasi merupakan yang tertinggi dalam elemen ekuitas dan memiliki persentase hingga 18,84%, sementara faktor pelestarian hutan merupakan yang tertinggi dalam elemen reduksi emisi dan memiliki persentase hanya sebesar 4,35% saja, sehingga apabila ditelaah lebih lanjut dari Tabel 4,
Sinergi Tata Ruang terhadap Pelaksanaan REDD+: ..... (Nugroho Adi Utomo & R.P. Sitorus)
173
urutan elemen dasar dan proses REDD+ yang ada dalam dokumen RPJPD Kabupaten Katingan 2005–2025 yang banyak kandungannya yaitu elemen manfaat tambahan, ekuitas dan reduksi emisi.
2) Elemen dasar dan proses REDD+ dalam dokumen RTRW Kabupaten Katingan 2011–2031
Hal yang sama juga dilakukan pada RTRW, hasil interpretasi analisis isi pada RTRW Kabupaten Katingan 2011–2031 juga ditentukan berdasarkan persentase kumulatif pada setiap faktor yang berpengaruh terhadap elemen dasar dan proses REDD+ secara menyeluruh (mulai dari Bab I hingga Bab VIII). Hasil interpretasinya dapat dilihat pada Tabel 5. Dalam setiap elemen dasar dan proses
REDD+, dapat dilihat faktor peningkatan kesejahteraan dan lingkungan dan biodiversitas (dalam elemen manfaat tambahan) merupakan faktor yang paling banyak kandungannya dalam dokumen RTRW, sama-sama bernilai 28,57%. Kemudian faktor transparansi dan partisipasi merupakan yang tertinggi dalam elemen ekuitas dan memiliki persentase hingga 14,29%, sementara faktor pelestarian hutan merupakan yang tertinggi dalam elemen reduksi emisi dan memiliki persen-tase sebesar 17,14%. Sehingga apabila ditelaah lebih lanjut dari Tabel 5, urutan elemen dasar dan proses REDD+ yang ada dalam dokumen RTRW Kabupaten Katingan 2011–2031 yaitu elemen manfaat tambahan, elemen reduksi emisi dan elemen ekuitas.
JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 165-176
Tabel 4. Interpretasi hasil analisis isi RPJPD Kabupaten Katingan tahun 2005-2025 Table 4. Result interpretation from content analysis of RPJPD Katingan District 2005-2025
Sumber (Source): Data diolah (Data processed), 2013
Kode (Code)
Rincian Kode (Detail Code)
Rasio (Ratio)
Interpretasi (Interpretation)
1. Kode 1 1a 0,00% Dalam elemen dasar dan proses REDD+, khususnya elemen reduksi emisi, faktor Pelestarian Hutan paling banyak diulas dalam RPJPD Kabupaten Katingan 2005 – 2025 1b 4,35%
2. Kode 2 2a 17,39% Dalam elemen dasar dan proses REDD+, khususnya elemen manfaat tambahan, faktor Peningkatan Kesejahteraan paling banyak diulas dalam RPJPD Kabupaten Katingan 2005 – 2025 2b 33,33%
3. Kode 3 3a 5,80% Dalam prinsip-prinsip REDD+, khususnya prinsip Kesetaraan, khususnya elemen ekuitas, faktor Transparansi dan Partisipasi paling banyak diulas dalam RPJPD Kabupaten Katingan 2005 – 2025 3b 13,04%
3c 18,84% 3d 7,25%
Sumber (Source): Data diolah (Data processed), 2013
Kode (Code)
Rincian kode (Detail code)
Rasio (Ratio)
Interpretasi (Interpretation)
1. Kode 1 1a 1,43% Dalam elemen dasar dan proses REDD+, khususnya elemen reduksi emisi, faktor Pelestarian Hutan paling banyak diulas dalam RTRW Kabupaten Katingan 2011-2031 1b 17,14%
2. Kode 2 2a 28,57%
Dalam elemen dasar dan proses REDD+, khususnya elemen manfaat tambahan, faktor Peningkatan Kesejahteraan - Kualitas Lingkungan dan Biodiversitas sama-sama paling banyak diulas dalam RTRW Kabupaten Katingan 2011-2031
2b 28,57%
3. Kode 3 3a 0,00% Dalam prinsip-prinsip REDD+, khususnya prinsip Kesetaraan, faktor Transparansi dan Partisipasi paling banyak diulas dalam RTRW Kabupaten Katingan 2011-2031
3b 7,14% 3c 14,29% 3d 2,86%
Tabel 5. Interpretasi hasil analisis isi RTRW Kabupaten Katingan tahun 2011 – 2031 Table 5. Result interpretation from content analysis of RTRW Katingan District 2011 – 2031
E. Preferensi Stakeholder atas Keberlanjutan Inisiatif REDD+ di Katingan
Pada bagian ini akan dibahas mengenai preferensi para pihak agar keberlanjutan inisiatif REDD+ yang sudah berjalan semakin baik lagi. Dari total 22 responden yang terpilih, dapat diketahui prioritas preferensi dari faktor-faktor dalam setiap aspek manfaat (langsung dan tidak langsung) dan biaya sosial (pertimbangan sosial) yang berpengaruh terhadap keberlanjutan inisiatif REDD+ di Kabupaten Katingan. Tabel 6 menunjukkan pengelompokkan sesuai aspek dan faktor mana saja tertinggi rasio bobotnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi responden untuk ketiga aspek tersebut adalah: Aspek manfaat langsung (lapangan pekerjaan); Aspek manfaat tidak langsung (berkurangnya bencana alam); Aspek biaya sosial-pertimbangan sosial (memilih faktor konflik antar masyarakat). Menurut penulis, apa yang dipilih responden cukup mewakili gambaran nyata di lapangan, masyarakat dan para pihak di Kabupaten Katingan khususnya sangat menaruh harapan pada inisiatif REDD+ yang bisa membuat masyarakat sejahtera dan berkontribusi positif terhadap perubahan iklim.
F. Arahan Penyempurnaan Kebijakan RTRW Kabupaten Katingan
Undang-Undang (UU) Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang memandatkan pemerintah kabupaten untuk segera menyelesaikan RTRW Kabupaten dalam waktu 2 (dua) tahun (Undang-Undang, 2007), namun hingga kini, baik provinsi
maupun Kabupaten Katingan belum mendapat-kan persetujuan. Permasalahannya adalah proses padu serasi antara RTRW Provinsi dengan kawasan hutan yang tidak berujung tuntas. Sejak Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1982 tidak pernah terjadi padu serasi, sampai akhirnya muncul SK Menteri Kehutanan Nomor SK. 529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/ 10/1982 tentang penunjukan areal hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah (Surat Keputusan Menteri Kehutanan, 2012b). yang melakukan revisi atas TGHK 1982. Sempat juga muncul pengajuan permohonan uji materi UU Nomor 41 tahun 1999 terhadap pasal 1 angka 3 pada UU Nomor 41 tahun 1999 (terkait definisi kawasan hutan) ke Mahkamah Konstitusi oleh Bupati Katingan bersama dengan Bupati Kapuas, Bupati Gunung Mas, Bupati Barito Timur, Bupati Sukamara dan 1 (satu) orang pengusaha di Palangkaraya, yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan para bupati tersebut. Di Kabupaten Katingan, Putusan MK ini berdampak pada beberapa izin perkebunan dan pertambangan yang berada di kawasan hutan menjadi bukan tindak pidana, mengingat seluruh kawasan hutan yang ada di Kalimantan Tengah belum dikukuhkan melalui tahapan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan (Pasal 15 ayat 1 UU Nomor 41 tahun 1999). Di lain sisi masuknya inisiatif REDD+ di Kabupaten Katingan sangat memerlukan kepastian rencana tata ruang wilayah yang tuntas, terlebih REDD+ erat sekali dengan kawasan hutan yang saat ini
174Sinergi Tata Ruang terhadap Pelaksanaan REDD+: ..... (Nugroho Adi Utomo & R.P. Sitorus)
Sumber (Source): Data diolah (Data processed), 2013
Aspek (Aspect)
Faktor-faktor dalam setiap aspek (Factors in each aspect)
Bobot preferensi (Preference weighted)
Persentase preferensi (Preference percentage)
Manfaat langsung - Lapangan pekerjaan 0,513 51,30% 1
- Tambahan penghasilan 0,487 48,70% 2
Manfaat tidak langsung - Rehabilitasi hutan 0,267 26,70% 2
- Berkurangnya bencana alam 0,277 27,70% 1
- Ketersediaan air tanah 0,216 21,60% 4
- Hasil hutan non kayu 0,240 24,00% 3
Biaya sosial - pertimbangan sosial
- Konflik antar pemerintah 0,286 28,60% 3
- Konflik pemerintah-masyarakat 0,350 35,00% 2
- Konflik antar masyarakat 0,364 36,40% 1
Tabel 6. Urutan preferensi gabungan seluruh responden Table 6. Sequence of total preference from all respondents
cenderung menurun luasannya sesuai hasil penelitian pada sub bab pola perubahan peng-gunaan lahan hutan terdahulu.
Dalam hal arahan penyempurnaan RTRW Kabupaten Katingan, berdasarkan hasil penelitian dan uraian proses sejarah revisi RTRW, baik Provinsi Kalimantan Tengah maupun Kabupaten Katingan, agar bisa berjalan bersama dan ter-integrasi dengan inisiatif REDD+ perlu memper-timbangkan beberapa hal berikut: 1. Secara keruangan, inisiatif REDD+ dalam
pengalokasian ruang sebaiknya dilakukan selain pada kawasan lindung juga pada kawasan hutan produksi terbatas di kawasan budi daya, mengingat hasil analisis inkonsistensi RTRW cukup besar terjadi pada kawasan budi daya.
2. Pemerintah Kabupaten Katingan perlu meng-upayakan penyelesaian RTRW yang disesuaikan dengan kebijakan terbaru terkait kawasan hutan dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Kehu-tanan Nomor SK. 529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 tentang penunjukan areal hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah SK 529/2012 (Surat Keputusan Menteri Kehu-tanan, 2012b). Upaya ini tentunya sekaligus mengakomodasi kepentingan Pemerintah Pusat, meskipun tetap masih ada status kawasan hutan yang belum jelas (holding zone) karena memang upaya penetapan kawasan hutannya belum dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh.
3. Mendeklarasikan Kabupaten Katingan sebagai Kabupaten Berkelanjutan (sustainable district) yang bertumpu kuat pada pilar ekonomi, sosial, lingkungan dan kelembagaan. Pernyataan ini sebaiknya ditambahkan pada visi dan misi perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Katingan. Hal ini diperlukan untuk menunjuk-kan komitmen pemerintah Kabupaten Katingan dalam merespon inisiatif REDD+ agar bisa berjalan semestinya.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam bagian pembahasan dapat disimpulkan, pertama, sejak tahun 2000 hingga 2012 berdasarkan analisis
citra satelit, penggunaan lahan hutan masih merupakan lahan yang paling dominan dimana saat ini mencapai 60,47% dari luasan kabupaten (1.242.554 ha) atau berkurang 13,05% sejak tahun 2000. Berkurangnya luasan kawasan hutan ini disebabkan adanya perubahan penggunaan lahan hutan menjadi penggunaan lainnya, yaitu peru-bahan hutan menjadi penggunaan lahan semak belukar/tanah terbuka terlebih dulu atau bisa langsung berubah ke penggunaan lahan tanaman tahunan (perkebunan), pertanian pangan lahan kering dan pemukiman, dan perubahan dari pertanian pangan lahan kering menjadi pengguna-an lahan pemukiman.
Kedua, inkonsistensi penggunaan lahan existing berdasarkan interpretasi citra yang dibandingkan dengan RTRW maupun kawasan hutan hasil keduanya menunjukkan luasan inkonsistensi yang relatif kecil. Hal ini terjadi karena masih belum sinkron antara RTRW dan kawasan hutan sendiri, sehingga mungkin mekanisme kontrol atas kondisi eksisting tidak bisa berjalan optimal.
Ketiga, secara kebijakan perencanaan daerah, Kabupaten Katingan yang telah memiliki RPJPD 2005–2025 dan draft RTRWK 2011–2031 nyatanya cukup baik dalam mengakomodasi elemen dasar dan proses REDD+. Hal ini berarti bahwa, secara kebijakan, Kabupaten Katingan telah memiliki dokumen yang mendukung dan tidak bertentangan apabila inisiatif REDD+ ini ingin dilanjutkan implementasinya.
Keempat, melalui Analytical Hierarchy Process (AHP) terlihat preferensi stakeholder atas keber-lanjutan inisiatif REDD+ melalui aspek manfaat langsung (lapangan pekerjaan), aspek manfaat tidak langsung (berkurangnya bencana alam) dan aspek biaya sosial (konflik antar masyarakat). Hasil ini juga menunjukkan stakeholder mendukung atas inisiatif REDD+ dengan harapan masyarakat bisa memperoleh manfaat langsung terutama pada tersedianya lapangan pekerjaan.
Kelima, arahan penyempurnaan RTRW agar sejalan dengan inisiatif REDD+, adalah: inisiatif REDD+ perlu memerhatikan kondisi eksisting yang telah digambarkan dalam RTRW Kabupaten dan dalam hal pengalokasian ruang, inisiatif REDD+ sebaiknya diakomodasi dalam RTRW pada kawasan lindung serta sebagian pada kawasan budidaya {kawasan hutan produksi (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT).
175JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 165-176
B. Saran
Beberapa saran yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan agar penerapan inisiatif REDD+ sejalan dengan RTRW adalah: 1. pentingnya menjaga kondisi tren penggunaan
lahan agar alokasi ruang inisiatif REDD+ bisa lebih berkelanjutan.
2. meningkatkan pemahaman kepada stakeholder terkait mengenai isu REDD+.
UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)
Penulis ingin memberikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Center for International Forestry Research (CIFOR), khususnya proyek Global Comparative Study on REDD+ (GCS-REDD) Module 2 yang dipimpin oleh Dr. William Sunderlin yang mendanai kegiatan penelitian ini. Terimakasih tak terhingga kepada Dr. Daju Resosudarmo yang membantu mengarahkan substansi penelitian ini dari awal hingga akhir. Tidak lupa juga penulis ingin memberikan apresiasi ke-pada seluruh pihak pemerintah daerah, khususnya Bappeda Kabupaten Katingan yang memberikan dukungan penuh dan para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas kontribusinya hingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik.
DAFTAR PUSTAKA
Angelsen, A., Brockhaus, M., Sunderlin, W. D., & Verchot, L. V. (2013). Menganalisis REDD+. Bogor: CIFOR.
Angelsen, A., Brown, S., Loisel, C., Peskett, L., Streck, C., & Zarin, D. (2009). Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD): an options assessment report (Vol. 6). Retrieved 27 Februari 2013 from http://www.redd-oar.org/ links/REDD-OAR_en.pdf.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan. (2010). Katingan dalam angka 2008/2009. Kasongan: Badan Pusat Statistika Kabupaten Katingan.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan. (2012). Katingan dalam angka 2012. Kasongan: Badan Pusat Statistika Kabupaten Katingan.
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Katingan. (2012). Statistik kehutanan Kabupaten Katingan tahun 2011. Kasongan: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Katingan.
Ekomadyo, A. S. (2006). Prospek penerapan metode analisis isi (content analysis). Jurnal Itenas: Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Seni 10(2):51-57.
Marimin. (2004). Teknik dan aplikasi pengambilan keputusan kriteria majemuk. Grasindo. http:// doi.org/10.13140/RG.2.1.3743.2800.
Niin. (2010). Dinamika spasial penggunaan lahan di Kabupaten Katingan dan Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Parnphumeesup, P., & Kerr, S. A. (2011). Stakeholder preferences towards the sustainable develop-ment of CDM projects: Lessons from biomass (rice husk) CDM project in Thailand. Energu Policy, 39(6), 35913601. http://doi.org/ 10.1016/ j.enpol.2011.03.060.
Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ Indonesia. (2012). Strategi Nasional REDD+. Jakarta: Bappenas.
Stern, N. (2006). Stern review: The economics of climate change. United Kongdom: Cambridge University Press. http://doi.org/10.1257/ aer.98.2.1.
Stern, Nicholas. (2008). Key elements of a global deal on climate change. London: London School of Economics and Political Science.
Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 660/302/ KPTS/XII/2011 Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengurangan Emisi dari Kegiatan Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) Kabupaten Katingan.
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6315/ Menhut-VII//IPSDH/2012 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi III).
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/ KPTS/UM/10/1982 tentang penunjukkan areal hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas ± 15.300.000 ha (SK 529/2012).
Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Yuris, A. (2009). Berkenalan dengan analisis isi (content analysis). Retrieved January 1, 2012, from https://andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/analisis-isi-content-analysis/
176Sinergi Tata Ruang terhadap Pelaksanaan REDD+: ..... (Nugroho Adi Utomo & R.P. Sitorus)
177
I. PENDAHULUAN
Pemanasan global dan perubahan iklim dalam dekade terakhir menjadi perhatian dan per-masalahan lingkungan dunia. Lingkungan per-kotaan disinyalir sebagai sumber penyumbang besar terjadinya pemanasan global (Sangkertadi, 2013). Pemanfaatan tata ruang yang ada di perkotaan
dikaitkan dengan proses pembangunan untuk memenuhi tuntutan dalam perkembangan kota. Kondisi ini makin diperparah dengan berbagai aktivitas masyarakat perkotaan yang tidak ramah lingkungan dan semakin berkurangnya vegetasi sebagai penahan radiasi matahari.
Perkembangan kota yang tidak terkontrol ini bila dibiarkan terus menerus dapat menimbulkan
ORIENTASI MASYARAKAT KOTA BOGOR TERHADAP NILAIKENYAMANAN UDARA
(The Orientation of Bogor's Society towardValue of Air Amenity)
Andry Saputra , Ricky Avenzora , Dudung Darusman , & Rachmad Hermawan1) 2) 3) 2)
1)Program Studi Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan, Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan
Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16001,Institut Pertanian Bogor
E-mail: [email protected]) Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB,
Kampus IPB Dramaga, Bogor 16001, IndonesiaE-mail: [email protected]; [email protected]
3) Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16001, IndonesiaE-mail: [email protected]
Diterima 4 Januari 2016, direvisi 15 Januari 2016, disetujui 16 November 2016
ABSTRACT
Public participation is needed to answer the limitation of fund in realizing the micro-climate amelioration program. This research aims to analyze the public perception on climate change in Bogor City, the air amenity index on micro-climate, and the value of willingness to pay (WTP) of community. Data was collected through questionnaires using One Score One Criteria method (Avenzora, 2008) and result was analyzed using statistics. The research showed that each village facing different problems related to the causes of the air amenity degradation. This result was also supported by the value of Temperature Humidity Index which was uncomfortable and according to the public perception that there was an increasing of the air temperature and humidity. The value of willingness to contribute of the community was /family/month which is accumulatively community participation potency of Bogor City estimated to reachRp12,413Rp3,220,453,546 per month.
Keywords: Air amenity; Bogor City; micro-climate; willingness to pay.
ABSTRAK
Partisipasi masyarakat diperlukan dalam menjawab keterbatasan dana untuk merealisasikan program ameliorasi iklim mikro. Penelitian bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap perubahan iklim Kota Bogor, indeks kenyamanan udara terhadap iklim mikro, dan nilai (WTP) masyarakat. Data willingness to pay diperoleh melalui kuesioner dengan metode yang kemudian hasilnya dianalisis secara statistik. One Score One Criteria Penelitian menunjukkan setiap kelurahan memiliki permasalahan yang berbeda terkait dengan faktor penyebab terjadinya degradasi kenyamanan udara. Hal ini didukung oleh nilai yang tidak nyaman dan Temperature Humidity Indexpersepsi dari masyarakat bahwa terjadi peningkatan suhu udara dan kelembapan udara. Hasil WTP menunjukkan Rp12.413/KK/bulan; yang secara akumulatif potensi partisipasi masyarakat Kota Bogor diestimasi mencapai jumlah Rp3.220.453.546 per bulan.
Kata kunci: Kenyamanan udara; Kota Bogor; iklim mikro; willingness to pay.
JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 177-187
178
Responden ditentukan dengan simple random sampling. Lokasi pengambilan sampel dimulai dari tingkat kecamatan dengan memilih sebanyak tiga kecamatan.
Penentuan kecamatan dilihat dari persentase areal pemukiman yang mewakili tiga kelas: rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan pada total luasan tutupan lahan Kota Bogor (Direktorat Inven-tarisasi dan Pemantauan SDH, 2011). Selanjutnya dipilih sejumlah tiga kelurahan per kecamatan yang mewakili tiga kelas kepadatan penduduk di tiap kelurahan: rendah, sedang, dan padat. Besaran ukuran sampel pada tiap kelurahan mengacu pada saran Roscoe (1982) Sugiyono (2009) yang dalam menyatakan bila sampel terbagi dalam kategori maka jumlah anggota sampel per kategori minimal 30 responden.
B. Alat dan Responden Penelitian
Alat yang digunakan adalah thermometer digital portable yang dilengkapi monitor pembacaan terhadap suhu udara dan kelembapan udara yaitu Corona dengan resolusi 0,1 C dan
® otemperaturehumidity software 1% RH, kuesioner, alat tulis, Microsoft Office Statistics . 2010 serta SPSS 15Responden penelitian adalah Kepala Keluarga (KK) di Kota Bogor sebanyak 270 Kepala Keluarga dengan responden tiap kelurahan sebanyak 30 KK.
C. Data Primer dan Analisis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner dengan metode One Score One Criteria (Avenzora, 2008). Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data jumlah penduduk Kota Bogor dan data tutupan lahan Kota Bogor. Data primer dan analisis data dalam penelitian ini tercantum dalam Tabel 1.
Analisis Kruskal Wallis digunakan untuk analisis komparatif yang memiliki lebih dari dua sampel yang independen dengan data berbentuk ordinal (Sugiyono, 2011), kemudian dilakukan uji lanjut dengan Uji Dunn untuk melihat faktor yang memengaruhi terkait dengan penyebab menurun-nya kenyamanan udara berdasarkan pada persepsi masyarakat di setiap kelurahan. Temperature Humidity Index (THI) merupakan nilai yang
degradasi kenyamanan udara perkotaan, salah satunya seperti yang dirasakan oleh masyarakat Kota Bogor. Badan Statistik (2013) mencatat dalam rentang waktu hanya setahun (2011-2012) suhu rata-rata Kota Bogor meningkat sebesar 0,3 C. o
Seiring dengan hal tersebut, masyarakat merin-dukan udara Kota Bogor yang sejuk seperti dulu (Leksonowati, 2013). Hal ini dapat mengindikasi-kan ketidaknyamanan udara Kota Bogor sehingga masyarakat mulai merasakan panas di Kota Bogor.
Keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam merealisasikan berbagai program dalam mem-perbaiki iklim mikro perkotaan. Dengan demikian, diperlukan partisipasi masyarakat dalam hal ini terkait dengan kesediaan mereka untuk membayar atau (WTP) sebagai upaya Willingness to Pay menjawab masalah pendanaan untuk merealisasi-kan program perbaikan iklim. Pendekatan kesediaan untuk membayar ( ) yang willingness to paydinilai secara moneter (uang) digunakan untuk memperoleh suatu peningkatan kondisi lingkungan dan menjadi lebih baik dari keadaan yang sebelumnya (Fauzi, 2010; Yakin, 1997).
Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis persepsi masyarakat terhadap perubahan iklim Kota Bogor, 2) menganalisis indeks kenyamanan udara terhadap iklim mikro masing-masing daerah, dan 3) menganalisis nilai (WTP) willingness to pay masyarakat sebagai upaya peningkatan kenyamanan udara Kota Bogor. Nilai kesediaan membayar yang diberikan oleh masyarakat dapat dijadikan estimasi dana lingkungan sebagai upaya peningkatan kenyamanan udara di Kota Bogor. Pemilihan Kota Bogor sebagai studi kasus partisipasi masyarakat perkotaan untuk memperbaiki (ameliorasi) iklim mikro Kota Bogor demi terciptanya udara nyaman kembali, diharapkan dapat menjadi contoh dalam menjawab tantangan perbaikan iklim di bumi.
II. METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu
Penelitian dilaksanakan pada Agustus sampai September 2014 di sembilan kelurahan di Kota Bogor yaitu: Bogor Barat (Curug Mekar, Loji, dan Pasir Kuda), Tanah Sareal (Kedung Badak, Kedung Waringin, dan Kebon Pedes), dan Bogor Tengah (Panaragan, Kebon Kalapa, dan Gudang).
Orientasi Masyarakat Kota Bogor terhadap Nilai ..... ( )Andry Saputra, Ricky Avenzora, Dudung Darusman, & Rachmad Hermawan
kelurahan memiliki perbedaan (Tabel 2). Hasil ini berdasarkan pada (rata-rata peringkat mean rank dari nilai persepsi masyarakat tiap kelurahan) terbesar dan memiliki yang sama pada subset mean rank besar dalam Uji Dunn.
Penyebab penurunan kenyamanan udara dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor makro dan faktor mikro. Faktor makro lebih memberikan dampak secara global dibandingkan dengan faktor mikro yang hanya berdampak pada daerah tertentu saja. Masyarakat memper-Kelurahan Kebon Pedessepsikan asap industri menjadi salah satu penyebab menurunnya kenyamanan udara . Hal di daerahnyaini disebabkan Kelurahan Kebon Pedes berdekatan langsung dengan areal industri (pabrik Good Year). Di daerah berbeda, emisi kendaraan sangat dirasakan masyarakat Kelurahan Loji dan Kebon Kalapa sebagai daerah yang banyak dilalui oleh kendaraan bermotor. Hal ini juga terlihat dari jumlah kendaraan bermotor yang melintas per jamnya (pukul 15.00-16.00) yaitu sebanyak 4.337 di Kelurahan Loji dan 4.064 di Kelurahan Kebon Kelapa.
Penumpukan sampah sangat mengganggu masyarakat di Kelurahan Kedung Waringin dan Kelurahan Pasir Kuda (Gambar 1). Penumpukan sampah ini lambat laun akan mengalami proses pembusukan secara alami dan dapat menimbulkan bau akibat terbentuknya gas metana (CH ) 4
(Wardhana, 2010). Pemakaian pupuk kimia pun
menunjukkan tingkat kenyamanan di suatu area secara kuantitatif. Pengukuran kenyamanan udara menggunakan indeks kenyamanan udara (McGregor & Nieuwolt, 1998).
THI =
Keterangan: T = Suhu udara ( C)
o RH = Kelembapan relatif (%)
Berdasarkan data iklim mikro (suhu dan kelembapan udara) akan diperoleh suatu tingkat kenyamanan udara dilihat dari indeks kenyamanan udara. McGregor and Nieuwolt (1998) menyatakan indeks kenyamanan secara umum dibagi menjadi 3 kondisi, yaitu nyaman (THI: 21−23), sedang/ sebagian orang menyatakan nyaman (THI: 24−25), dan tidak nyaman (THI: > 26).
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Persepsi Masyarakat
Persepsi merupakan penilaian yang diberikan seseorang mengenai objek tertentu melalui proses penginderaannya (Sarwono, 1992). Bila hal ini dikaitkan dengan faktor penyebab degradasi kenyamanan udara di perkotaan, hasil analisis Uji Dunn menunjukkan persepsi masyarakat di setiap
179
Tabel 1. Data primer dan analisis dataTable 1. Primary data and data analysis
Aspek Penelitian (Aspect of research)
Pengumpulan Data (Data collection)
Data Primer (Primary data)
Analisis Data (Data analysis)
Persepsi masyarakat (Perception of public)
Kuesioner Persepsi masyarakat terhadap penyebab penurunan kenyamanan udara Persepsi masyarakat terhadap manfaat RTH Persepsi masyarakat terhadap suhu dan kelembapan udara (saat awal dan saat ini)
Kruskal Wallis dan Uji Dunn
Analisis deskriptif
Wilcoxon Match Pairs Test
Iklim mikro (Micro climate)
Pengukuran di lapangan
Suhu dan kelembapan udara aktual Data iklim dari Stasiun Klimatologi Baranangsiang
Temperature Humidity Index (THI) Analisis deskriptif
Nilai ekonomi kenyamanan udara (Economic value of air amenity)
Kuesioner Willingness to pay masyarakat Tingkat pendidikan Pendapatan Kategori penduduk Lama domisili
Regresi linear berganda WTP rata-rata
Sumber ( ): Avenzora, 2008; Sugiyono, 2009; Sugiyono, 2011; McGregor and Nieuwolt, 1998. Source
(0.8T ) + RH x T500 ))
JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 177-187
juga dapat memicu terbentuknya amonia (NH ) 3
karena adanya endapan nitrogen dari pemakaian pupuk kimia tersebut (Team SOS, 2011). Hal ini dapat menjadi permasalahan jika masyarakat setempat masih menggunakan pupuk kimia dalam bercocok tanam, seperti persepsi masyarakat Kelurahan Curug Mekar, Pasir Kuda dan Loji.
Kebijakan pemerintah terkait tata ruang kota seperti yang tertera pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor (2011) mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor juga dapat memengaruhi kenyamanan udara di perkotaan. Sebagai contoh, di Bogor Tengah sebagai pusat kota dan Tanah Sareal sebagai daerah pemukiman serta kegiatan perdagangan dan jasa sehingga marak
terjadinya alih fungsi lahan. Di Bogor Tengah khususnya Kelurahan Gudang, masyarakat mem-persepsikan alih fungsi lahan dan pertambahan penduduk menjadi faktor utama penyebab menurunnya kenyamanan udara. Di daerah berbeda, Kelurahan Kebon Pedes yang merupakan bagian dari Tanah Sareal menjadi daerah yang mengalami perubahan fungsi lahan yang pesat menurut persepsi masyarakat. Walaupun begitu, Kelurahan Kebon Pedes masih memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) lebih baik dibandingkan dengan Kedung Badak yang juga termasuk dalam wilayah Tanah Sareal. Selain Kedung Badak, berkurangnya RTH juga menjadi perhatian bagi masyarakat Kelurahan Loji.
180Orientasi Masyarakat Kota Bogor terhadap Nilai ..... ( )Andry Saputra, Ricky Avenzora, Dudung Darusman, & Rachmad Hermawan
Tabel 2. Persepsi masyarakat terhadap penyebab degradasi kenyamanan udara Table 2. Public perception toward the causes of air amenitydegradation
Faktor (Factor )
Persepsi (Perception )
Kelurahan (Village )
Rata -rata peringkat (Mean Rank )
Makro (Macro )
Asap industri Kebon Pedes 209,85 Pembusukan sampah Pasir Kuda
Kedung Waringin 178,57 188,67
Emisi kendaraan Loji Kebon Kalapa
158,58 163,15
Pemakaian pupuk Curug Mekar Pasir Kuda Loji
164,92 171,58 173,48
Mikro (Micro )
Alih fungsi lahan Gudang Kebon Pedes
166,80 175,70
RTH berkurang Loji Kedung Badak
178,00 189,47
Pertambahan penduduk Gudang 172,98 Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2014
Gambar 1. Penumpukan sampah di Kedung WaringinFigure 1. Stacking crap in KedungWaringin
Sumber (Source): Dokumentasi pribadi (2014)
181
Degradasi kenyamanan udara akibat faktor makro dan mikro tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat. Suhu udara dan kelembapan udara merupakan parameter iklim yang biasa digunakan dalam masalah kenyamanan udara (Frick & Sukiyanto, 2007). Persepsi masyarakat terhadap cuaca didasarkan pada kenyamanan termal. Kebasahan kulit oleh keringat juga dapat dijadikan parameter dalam menentukan kenyamanan termal (Sangkertadi, 2013).
Analisis Wilcoxon Match Pairs Test (ρ-value 0,000<α=0,05) menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi masyarakat terhadap cuaca (suhu udara dan kelembapan udara) awal dan saat ini. Perbedaan persepsi masyarakat terhadap suhu udara ditunjukkan dengan adanya pening-katan suhu udara saat ini dibandingkan saat awal mereka tinggal di kelurahan tersebut. Persepsi perbedaan kelembapan udara dilihat dari tingkat kebasahan kulit oleh keringat. Saat ini masyarakat merasakan lebih berkeringat dibandingkan dengan awal mereka tinggal di kelurahan tersebut yang cenderung kering (tidak berkeringat). Hal ini berarti saat ini kelembapan udara mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kelembapan udara saat awal. Frick & Sukiyanto (2007) menyatakan kelembapan udara yang tinggi mengakibatkan sulit terjadinya penguapan di permukaan kulit. Bila kelembapan udara rendah, orang akan merasakan udara yang kering.
Pembangunan dan pengembangan RTH menjadi solusi dalam memperbaiki iklim mikro perkotaan. Masyarakat menyadari dengan adanya pembangunan dan pengembangan RTH di Kota Bogor dapat memberikan manfaat langsung bagi mereka untuk mendapatkan udara sejuk dan segar (71,5%). Selain itu, secara tidak langsung masyarakat menyadari RTH dapat menurunkan suhu udara dan meningkatkan kelembapan udara (61,5%). Persepsi masyarakat terhadap keberadaan RTH senada dengan hasil penelitian Yan, Wang, Hao, and Dong (2012) di Beijing Olympic Forestry Park dengan luasan 680 Ha yang menunjukkan vegetasi dapat menurunkan suhu udara 1,6–2,5°C dan meningkatkan kelembapan udara 2,9%–5,2%.
Pepohonan yang memiliki kanopi yang lebar akan efektif dalam ameliorasi iklim mikro dan menurunkan suhu udara sebagai kontrol kenyamanan termal (Nasir, Ahmad, Zain-Ahmed, & Ibrahim, 2015). Keberadaan RTH dapat
memberikan dampak pada penurunan suhu permukaan tanah, seperti hasil penelitian (Buyadi, Wan Mohd, and Misni (2013) berdasarkan analisis citra satelit, menunjukkan konversi lahan hijau menjadi perumahan secara signifikan meningkat-kan suhu permukaan tanah dan tutupan lahan yang didominasi oleh RTH dapat membantu dalam mengurangi suhu permukaan tanah.Vegetasi pohon mampu mereduksi suhu udara sebesar 0,86–5,15°C lebih besar dibandingkan dengan vegetasi lainnya (semak dan rumput) (Ainy, 2012; Zain et al., 2015).
B. Indeks Kenyamanan Udara terhadap Iklim Mikro
Iklim mikro dapat diartikan kondisi iklim pada suatu ruang sempit yang berada pada ketinggian ± 2 meter (Frick & Sukiyanto, 2007). McGregor and Nieuwolt (1998) menyatakan indeks kenyamanan dalam kondisi nyaman ideal daerah tropis berada pada kisaran Temperature Humidity Index (THI) 21-26. Suhu udara dan kelembapan udara merupakan faktor iklim yang digunakan dalam menentukan THI (Tabel 3).
Perubahan suhu udara dan kelembapan udara akan memengaruhi nilai THI daerah tersebut. Nilai koefisien positif (+) pada persamaan regresi THI = -0,650 + 0,826 T + 0,058 RH, menunjukkan meningkatnya suhu udara (T) dan kelembapan udara (RH) akan meningkatkan THI. Nilai THI yang meningkat mengindikasikan daerah tersebut semakin tidak nyaman.
Data iklim mikro di sembilan kelurahan menunjukkan suhu udara berkisar antara 27–33 C. o
Dengan demikian, kisaran suhu udara tersebut termasuk ke dalam klasifikasi agak panas hingga sangat panas (27,1-≥31,1) (Setyowati & Sedyawati, 2010). Hal ini menunjukkan lokasi penelitian tersebut memiliki iklim mikro (suhu udara) yang sudah tidak nyaman bagi manusia. Data THI di sembilan kelurahan menunjukkan kelembapan udara antara 41%–64% sehingga kisaran kelembapan udara tersebut termasuk ke dalam klasifikasi kering (<70%) (Setyowati & Sedyawati, 2010).
Perhitungan THI di sembilan kelurahan didominasi dengan klasifikasi tidak nyaman (THI>26) baik pagi, siang, sore, maupun malam.Perhitungan THI ternyata berbanding lurus dengan persepsi masyarakat. Saat ini
JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 177-187
182
Tabel 3. Nilai THI di setiap kelurahan Table 3. Value of THI in every village
masyarakat merasakan ada peningkatan suhu udara dan kelembapan udara di masing-masing kelurahan. Hal ini juga didukung data dari Stasiun Klimatologi Baranangsiang FMIPA-IPB yang memperlihatkan adanya peningkatan suhu udara, kelembapan udara,
dan curah hujan dalam kurun waktu limatahun (Tabel 4). Kelembapan udara juga dipengaruhi oleh curah hujan. Sangkertadi (2013) menyatakan curah hujan yang tinggi akan menyebabkan kelembapan udara di daerah tersebut akan tinggi pula.
Orientasi Masyarakat Kota Bogor terhadap Nilai ..... ( )Andry Saputra, Ricky Avenzora, Dudung Darusman, & Rachmad Hermawan
Kecamatan (Subdistrict)
Kelurahan (Village)
Rerata (Average) Pagi
(morning) Siang (noon)
Sore (afternoon)
Malam (night)
T RH T RH T RH T RH
Bogor Barat
Curug mekar 30 60 33 49 31 49 30 57 27,57* 29,36* 28,28* 27,81*
TN TN TN TN Loji 29 55 32 45 32 46 28 64
26,50* 28,19* 28,18* 26,26* TN TN TN TN
Pasir Kuda 30 51 33 41 31 43 27 61 27,25* 28,83* 27,58* 25,03*
TN TN TN SG
Tanah Sareal
Kedung Badak 30 48 32 49 32 49 29 61 27,16*
28,42*
28,69*
26,98*
TN
TN
TN
TN
Kedung Waringin
31
48
32
39
32
43
30
46
27,50*
28,06*
28,19*
26,33*
TN
TN
TN
TN
Kebon Pedes
30
57
33
40
30
46
30
63 27,22*
28,81*
26,91*
27,55*
TN
T N
TN
TN
Bogor Tengah
Panaragan
29
55
32
43
31
47
30
60 26,43*
28,47*
27,60*
27,16*
TN
TN
TN
TN Kebon Kalapa
30
49
33
46
32
44
30
55
26,72*
29,22*
28,47*
27,04* TN
TN
TN
TN
Gudang
30
55
32
48
31
51
30
61 27,00*
28,81*
28,17*
28,09*
TN
TN
TN
TN Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2014
Tabel 4. Perbedaan suhu udara, kelembapan udara, curah hujan dalam lima tahun
Table 4. Air temperature, humidity, and rainfall variationduring interval 5 years
Musim
(Season)
Bulan
(Month)
Suhu (oC)
(Temperature) Kelembapan
(%)
(Humidity) Curah Hujan
(mm)
(Rainfall)
2008-2009
2013-2014
2008-2009
2013-2014
2008-2009
2013-2014
Musim Hujan
(Rainy season)
Oktober
26,5
27,1
79
77
334
461
November 25,6 26,8 79 76 534 249
Desember 24,9 26,1 82 81 300 574
Januari 24,0 24,4 84 89 481 835
Februari 24,0 25,1 85 86 283 476
Maret 25,5 26,4 84 84 380 505
Musim Kemarau (Dry season)
April 25,7 27,3 82 80 411 367
Mei 25,5 27,4 80 81 305 432
Juni 25,5 27,1 76 79 302 260
Juli 25,1 26,7 71 78 335 366
Agustus 25,4 26,7 71 74 63 395 September 26,2 27,2 72 70 356 68
Sumber (Source): Stasiun Klimatologi Baranangsiang FMIPA-IPB (Climatology Baranangsiang FMIPA-IPB station)
183
C. Willingness to Pay dalam Meningkatkan Kenyamanan Udara
Penilaian yang melibatkan jasa lingkungan dan sumber daya alam (SDA) yang tidak memiliki harga pasar, diperlukan suatu pendekatan dalam mengukur karakteristik dari SDA tersebut. Metode Stated Preference (SP) digunakan dalam mengukur karakteristik tersebut. Ada dua pendekatan pada metode SP yaitu (CVM) Contingent Valuation Method dan (CE) (Fauzi, 2014). Choice ExperimentPengukuran besarnya nilai kenyamanan udara dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan.
1. (WTP) berdasarkan pada Willingness to Pay kebebasan responden untuk menyatakan nilai moneter (rupiah yang bersedia dibayarkan).Skenario yang digunakan untuk mendapatkan
nilai kenyamanan udara diperoleh dari WTP masyarakat dalam hal pembangunan/pengem-bangan RTH sebagai upaya meningkatkan
kenyamanan udara di kelurahan responden. Masyarakat di setiap kelurahan memiliki rataan WTP yang berbeda-beda. WTP yang diberikan oleh masyarakat secara keseluruhan memiliki rata-rata Rp12.413/KK/bulan.
Namun tidak dipungkiri ada beberapa alasan yang melatarbelakangi masyarakat tidak memberi-kan WTP. Keterbatasan lahan untuk pembangunan dan pengembangan RTH (54,1%) dan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan RTH (37,4%) menjadi alasan masyarakat tidak bersedia untuk berkontribusi.
Analisis statistik secara keseluruhan menun-jukkan variabel-variabel penjelas dengan meng-gunakan variabel memengaruhi nilai WTP dummy responden. Model regresi linear berganda tersebut ditransformasikan (Ln) agar memenuhi uji normalitas, multikolinieritas, dan heteros-kedastisitas-nya sehingga ada beberapa variabel yang tereliminasi (Tabel 5).
Kelurahan (Village)
R2 Model Regresi
(Regression Model) Curug Mekar 0,799 Ln WTP = 10,374 – 1,671 X1 + 0,243 X3 + 1,000 X5– 1,675 X8 – 0,545 X9 –
0,352 X10 + 0,107 X11+ 0,615 X13 – 0,334 Ln X14
Loji 0,395 Ln WTP = 12,041 – 0,713 X1 + 0,324 X3 – 0,108 X4 + 1,278 X5 – 0,030 X8 + 0,294 X9 + 0,890 X10 + 0,618 X11 + 1,043 X13 – 1,123 Ln X14
Pasir Kuda 0,733 Ln WTP = 9,781 – 1,129 X1 + 0,322 X3 + 0,567 X4 – 0,969 X8– 0,907 X9 – 0,381 X10 – 0,494 X11 + 0,016 X13 – 0,025 Ln X14
Kedung Badak 0,424 Ln WTP = 10,091 – 0,464 X1 + 0,119 X2 + 0,157 X4 – 0,532 X8 – 1,048 X9 – 0,657 X10 + 0,410 X11 + 0,879 X13 – 0,261 Ln X14
Kedung Waringin 0,771 Ln WTP = 10,200 + 0,536 X1 + 0,107 X3 + 1,890 X5 – 0,518 X8 + 0,070 X9 + 0,520 X11+ 0,518 X13 – 0,500 Ln X14
Kebon Pedes 0,760 Ln WTP = 7,893 + 0,689 X 2 + 1,291 X3 – 0,336 X8 – 0,025 X9 + 0,559 X11 + 0,074 X13 – 0,042 Ln X14
Panaragan 0,630 Ln WTP = 10,038 – 1,569 X1 – 1,099 X2 + 0,647 X3 – 0,591 X4 – 0,963 X8 + 0,542 X9 + 0,599 X10 + 0,183 X11+ 0,782 X13– 0,374 Ln X14
Kebon Kalapa 0,364 Ln WTP = 9,806 – 0,715 X1 + 0,580 X3 + 1,039 X4 – 0,068 X9 – 0,490 X10 + 0,416 X13 – 0,291 Ln X14
Gudang 0,473 Ln WTP = 8,403 + 0,528 X 2 + 0,851 X3– 0,352 X9 – 0,023 X10 – 0,321 X13 + 0,018 Ln X14
Tabel 5. Hasil analisis WTP Table 5. Result of WTP analysis
WTP = Exp Ln WTP Keterangan (Remark):
X1= Penghasilan < Rp1.000.000 X2= Penghasilan Rp1.000.000 - < Rp2.000.000X3= Penghasilan Rp2.000.000 - < Rp4.000.000 X4= Penghasilan Rp4.000.000 - < Rp6.000.000X5= Penghasilan Rp6.000.000 - < Rp8.000.000X6 = Penghasilan Rp8.000.000 - < Rp10.000.000X7= Penghasilan > Rp10.000.000
X8 = SD/MI X9 = SMP/MTs X10 = SMA/SMK X11 = Diploma X12 = Sarjana X13 = Kategori penduduk X14 = Lama domisili
Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2014
JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 177-187
184
Tabel 5 menunjukkan apabila variabel tingkat pendapatan yang bernilai koefisien positif (+) mengartikan meningkatnya pendapatan responden akan memberikan nilai WTP yang tinggi pula. Koefisien tingkat pendidikan bila bernilai positif (+), berarti ketika tingkat pendidikan semakin tinggi maka WTP juga akan bertambah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan meningkatkan pemahaman seseorang terhadap pentingnya pembangunan dan pengembangan RTH agar dapat meningkatkan kenyamanan udara di lingkungannya. Dengan demikian, responden akan memberikan dana lebih untuk mewujudkan hal tersebut.
Kategori penduduk bernilai koefisien positif (+) berarti kategori penduduk asli (1) akan memberikan WTP yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk migran (0). Penduduk asli di kelurahan tersebut memberikan nilai WTP yang lebih tinggi agar mereka dapat merasakan kembali udara yang nyaman seperti awal mereka tinggal di sana. Variabel lama domisili yang bernilai koefisien positif (+) menunjukkan jika lama domisili bertambah 1 tahun maka nilai WTP akan meningkat. Hal ini dikarenakan masyarakat yang telah lama tinggal ingin merasakan udara nyaman seperti awal mereka tinggal di kelurahan tersebut, sehingga WTP yang mereka berikan juga akan semakin tinggi.
1. Willingness to Pay tidak langsung (berdasarkan pendapat responden terhadap kemampuan masyarakat sekitar).
Pendekatan ini untuk memberikan gambaran minimal WTP yang diberikan oleh responden. Kelurahan Kedung Waringin memiliki rataan WTP tertinggi (Rp6.433), sedangkan Kebon Pedes memiliki rataan WTP terendah (Rp3.600). Sebagian besar masyarakat mempercayakan dana yang diperuntukkan untuk pembangunan dan pengem-bangan RTH sebaiknya dikelola oleh masyarakat.
2. Willingness to Pay Choice berdasarkan pendekatan Experiment (CE).
Choice Experiment (CE) digunakan untuk mengukur nilai berdasarkan pada tawaran pilihan yang setiap pilihan memiliki karakteristik masing-masing (Fauzi, 2014). Nilai yang diberikan berdasarkan pada alokasi dana dari barang substitusi. Barang substitusi terkait dengan usaha
yang dilakukan oleh responden dalam memodi-fikasi iklim mikro di tempat tinggal mereka untuk menciptakan udara yang nyaman. Upaya meninggi-kan rumah memiliki alokasi dana tertinggi (Rp58.682.540) yang dilakukan responden dalam mendapatkan udara nyaman dibandingkan dengan menanam pepohonan atau tanaman di halaman rumah (Rp64.068). Menanam pepohonan atau tanaman selain biaya lebih murah dalam men-dapatkan udara nyaman, juga merupakan langkah alami dan ramah lingkungan dalam jangka panjang agar kenyamanan udara di lingkungan dapat tetap terjaga.
Secara keseluruhan, masih banyak masyarakat yang telah dan merencanakan menanam pepohonan atau tanaman pot dalam memodifikasi iklim mikro di tempat tinggal merekamenunjukkan masih ada rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan dapat berpotensi dalam upaya memperbaiki iklim mikro (ameliorasi) di Kota Bogor.
Keberadaan RTH sangat membantu dalam mengurangi persentase gas rumah kaca. Lukmanniah (2011) melalui penelitiannya menun-jukkan luas kanopi pohon dapat memengaruhi besarnya kapasitas karbon yang tersimpan dan daya serap karbon. Kemampuan pohon dalam menyimpan dan menyerap CO berbanding lurus 2
dengan persentase luas kanopi dan umur pohon.Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan
menjadi sinyal bahwa masyarakat merindukan “Kota Hujan” yang melekat pada Kota Bogor dengan udara sejuk dapat dirasakan kembali. Partisipasi masyarakat dengan memberikan kontribusi dalam pembangunan dan pengem-bangan RTH dapat menjadi solusi terhadap perbaikan iklim mikro di Kota Bogor.
A. Rumusan Kebijakan
Hasil evaluasi penerapan kota hijau di Kota Bogor yang dilakukan oleh Desdyanza (2014) menunjukkan realisasi konsep green planning and design di Kota Bogor masih belum maksimal. Dengan demikian, perlu adanya realisasi dalam penambahan RTH seperti yang telah diamanatkan dalam Perda Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M Tahun 2008 terkait dengan ketentuan minimum Koefisien Daerah Hijau (KDH) untuk memenuhi kebutuhan RTH Kota Bogor.
Orientasi Masyarakat Kota Bogor terhadap Nilai ..... ( )Andry Saputra, Ricky Avenzora, Dudung Darusman, & Rachmad Hermawan
185
Keterbatasan lahan yang menjadi persoalan dalam menambah RTH dapat diatasi, salah satu strateginya adalah dengan mengakuisisi RTH privat sebagai RTH kota. Joga and Ismaun (2011) mengemukakan perlu peraturan terkait dengan pelaksanaan Koefisien Dasar Hijau (KDH) pada lahan privat milik masyarakat dan swasta yang dapat diterapkan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pemerintah daerah dapat mendata, meningkatkan, dan menetapkan RTH privat sebagai bagian RTH. Dalam rencana RTRW, data RTH privat dapat dimasukkan dan ditetapkan sebagai bagian dari RTH kota. Selain itu, perlu adanya peraturan daerah yang mengatur hak dan kewajiban pemilik RTH privat, ketentuan luasan minimal RTH privat yang bisa diakuisisi, lokasi atau kawasan peruntukan RTH privat, serta insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemilik RTH privat.
Besaran rata-rata kontribusi masyarakat sejumlah Rp12.413/KK/bulan dapat digunakan dalam penerapan iuran lingkungan. Penerapan iuran lingkungan diharapkan sebagai dana untuk pembangunan dan pengembangan RTH demi memperbaiki (ameliorasi) iklim mikro di Kota Bogor.
Iuran lingkungan tersebut merupakan dana swadaya dari masyarakat sehingga diperlukan suatu lembaga untuk memegangperanan penting dalam menjalankan dan mengawal program pengelolaan dana masyarakat secara mandiri. Dalam hal ini, lembaga tersebut merupakan badan usaha non profit yang terbentuk atas inisiatif dari masyarakat berdasarkan pada diskusi publik atau Focus Group Discussion (FGD) antara tokoh-tokoh masyarakat dan unsur lembaga kemasyarakatan yang ada di Kota Bogor.
Badan usaha non profit ini merupakan forum bersama dan dapat terdiri atas perwakilan unsur-unsur lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan serta tokoh masyarakat. Lembaga ini sebagai penanggung jawab baik dalam proses perencanaan program, pelaksanaan program, maupun penggalangan kontribusi dari masyarakat untuk program pembangunan dan pengembangan RTH yang berada di tingkat kota. Adapun untuk legitimasi pembentukan lembaga berdasarkan Akta Notaris yang kemudian didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan usaha non profit. Akta Notaris
memuat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga lembaga, struktur lembaga, besaran kontri-busi yang telah disepakati oleh masyarakat, dan hal-hal yang terkait dengan lembaga. Kemudian, untuk iuran lingkungan ini dapat disosialisasikan dalam bentuk surat edaran/pemberitahuan yang dikeluar-kan oleh pihak RT/RW setempat.
Mekanisme pengumpulan dana dari masyarakat dilakukan melalui unit-unit yang berada di setiap kelurahan dan kemudian diserahkan ke lembaga di setiap awal bulan. Unit-unit tersebut bagian dari lembaga untuk penggalangan dana dari masyarakat dan menampung aspirasi/usulan masyarakat di tingkat kelurahan. Unit-unit ini dapat terdiri atas perwakilan tokoh masyarakat setempat dan unsur-unsur lembaga kemasyarakatan kelurahan.
Dana masyarakat tersebut digunakan untuk mengimplementasikan beberapa program ameliorasi iklim mikro Kota Bogor dalam kurun waktu 5 tahun. Beberapa program tersebut terkait dengan (1) pembangunan dan pengembangan RTH yang meliputi: pembangunan taman di enam kecamatan, pembangunan RTH pedestrian, penanaman di sempadan sungai dan rel kereta api, serta penanaman jalur hijau di sisi kanan dan kiri jalan, (2) pengelolaan sampah dengan pengadaan kontainer sampah ukuran 10 m sebanyak tiga unit 3
per kelurahan, dan (3) pengadaan mesin bor biopori untuk pembuatan lubang biopori di lingkungan rumah.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Hasil studi terhadap persepsi masyarakat menunjukkan adanya perbedaan persepsi tentang penyebab terjadinya degradasi kenyamanan udara di setiap kelurahan terkait faktor makro dan mikro. Perbedaan tersebut mempermudah dalam meng-klasifikasikan permasalahan setiap kelurahan sehingga informasi ini menjadi penting sebagai pedoman kebijakan dalam mengeliminir dampak negatif dari permasalahan yang terjadi di setiap kelurahan.
Persepsi masyarakat terkait iklim mikro secara signifikan menunjukkan saat ini telah terjadi peningkatan suhu udara dan kelembapan udara yang diindikasikan dengan saat ini masyarakat lebih berkeringat dibandingkan dengan saat awal mereka
JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 177-187
tinggal di kelurahan tersebut. Indikasi ketidak-nyamanan yang dirasakan masyarakat tersebut dapat menjadi acuan dalam menciptakan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat
Degradasi kenyamanan udara di Kota Bogor juga ditunjukkan oleh perhitungan Temperature Humidity Indeks (THI) McGregor&Nieuwolt yang didominasi oleh kriteria tidak nyaman (>26). Indeks THI menunjukkan tingkat kenyamanan di suatu area secara kuantitatif. Nilai THI ini dipengaruhi
ooleh besarnya suhu udara ( C) dan kelembapan udara (%). Peningkatan suhu udara dan kelembapan udara akan meningkatkan THI. Nilai THI yang meningkat mengindikasikan daerah tersebut semakin tidak nyaman.
Persepsi masyarakat yang merasakan ketidak-nyamanan terhadap iklim mikro lingkungannya akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam ameliorasi iklim mikro Kota Bogor. Partisipasi ini terlihat dari rataan kontribusi yang diberikan masyarakat dengan pendekatan WTP langsung sejumlah Rp12.413/KK/bulan untuk membangun dan mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Secara akumulatif - bila diasumsikan penduduk (KK) Kota Bogor pada tahun 2011 sebanyak 259.442 KK- estimasi potensi partisipasi masyarakat Kota Bogor sejumlah Rp3.220.453.546 per bulan atau sejumlah Rp38.645.442.552 per tahun. Dengan adanya potensi tersebut dapat menjadi modal penting dalam mitigasi iklim secara swadaya untuk meningkatkan kenyamanan udara Kota Bogor.
Implementasi dana masyarakat terlihat dari adanya beberapa program yang dapat dilakukan untuk ameliorasi iklim mikro Kota Bogor dalam kurun waktu 5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan swadaya masyarakat dapat menjawab keterbatasan dana yang selama ini menjadi kendala dalam merealisasikan berbagai program ameliorasi iklim mikro di perkotaan.
B. Saran
Perlu dilakukan penelitian serupa pada berbagai daerah lain agar potensi partisipasi masyarakat untuk ameliorasi iklim mikro dapat diprediksi di berbagai daerah dan secara nasional. Kemudian, karena menyangkut pengelolaan dana masyarakat yang besar jumlahnya maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mencari bentuk format lembaga yang terbaik untuk mengimplementasikannya.
UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan yang telah bersedia memberikan data terkait tutupan lahan Kota Bogor, serta Stasiun Klimatologi Baranangsiang FMIPA-IPB yang bersedia memberikan data terkait dengan suhu udara, kelembapan udara, dan curah hujan Kota Bogor. Kemudian, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor atas kesediaannya memberikan data terkait dengan jumlah penduduk Kota Bogor.
DAFTAR PUSTAKA
Ainy, C. N. (2012). Pengaruh ruang terbuka hijau terhadap iklim mikro di kawasan Kota Bogor. (Skripsi). Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Badan Pusat Statistik. (2013). Kota Bogor dalam angka tahun 2013. Bogor: Badan Pusat Statistik.
Buyadi, S. N. A., Wan Mohd, W. M. N., & Misni, A. (2013). Green spaces growth impact on the urban microclimate. Procedia-Social and Behavioral S c i en c e s , 105 , 547-557 . do i :10 .1016/ j.sbspro.2013.11.058.
Desdyanza, N. A. (2014). Evaluasi penerapan konsep kota hijau di Kota Bogor. (Skripsi). Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan SDH. (2011). Peta penutupan lahan Kota Bogor. Bogor: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan SDH.
Fauzi, A. (2010). Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan teori dan aplikasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Fauzi, A. (2014). Valuasi ekonomi dan penilaian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Bogor: IPB Press.
Frick, H., & Sukiyanto, F. B. (2007). Dasar-dasar arsitektur ekologis. Semarang: Kanisius.
Joga, N., & Ismaun, I. (2011). RTH 30% resolusi (kota) hijau. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Leksonowati, A. (2013). Bogor bukan kota yang nyaman ( l a g i ) . R e t r i e v e d f r o m h t t p : / 553019866ea834d4268b4582.
Lukmanniah, P. (2011). Manfaat kanopi pohon dalam upaya penyimpanan dan penyerapan karbon di kawasan
186Orientasi Masyarakat Kota Bogor terhadap Nilai ..... ( )Andry Saputra, Ricky Avenzora, Dudung Darusman, & Rachmad Hermawan
perumahan Kota Bogor. (Skripsi). Bogor: Institut Pertanian Bogor.
McGregor, G. R., & Nieuwolt, S. (1998). Tropical climatologi, an introduction to the climates of the low latitude. New York, USA: John Wiley & Sons.
Nasir, R. A., Ahmad, S. S., Zain-Ahmed, A., & Ibrahim, N. (2015). Adapting human comfort in a urban area: the role of tree shades towards urban regeneration. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 170, 369-380.doi:10.1016/ j.sbspro.2015.01.047.
Sangkertadi. (2013). Kenyamanan termis di ruang luar beriklim tropis lembap. Bandung: Alfabeta.
Sarwono, S. W. (1992). Psikologi lingkungan. Jakarta: PT. Grasindo.
Setyowati, D. L., & Sedyawati, S. M. R. (2010). Sebaran ruang terbuka hijau dan peluang perbaikan iklim mikro di Semarang Barat. Biosaintifika, 2(2), 61-74.
Sugiyono. (2009). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2011). Statistika non parametric. Bandung: Alfabeta.
Team SOS. (2011). Pemasangan global solusi dan peluang bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Wardhana, W. A. (2010). Dampak pemanasan global. Yogyakarta: ANDI.
Yakin, A. (1997). Ekonomi sumber daya dan lingkungan: teori dan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Jakarta: Akademika Presindo.
Yan, H., Wang, X., Hao, P., & Dong, L. (2012). Study on the microclimatic characteristic and human comfort of park plant communities in summer. Procedia-Environmental Sciences, 13, 755-765. doi:10.1016/j.proenv.2012.01.069.
Zain, A. F., Permatasari, P. A., Ainy, C. N., Destriana, N., Mulyati, D. F., & Edi, S. (2015). The detection of urban open space at Jakarta, Bogor, Depok, and Tangerang-Indonesia by using remote sensing technique for urban ecology analysis. Procedia-E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e s , 2 4 , 8 7 - 9 4 . doi:10.1016/j.proenv.2015.03.012.
187JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 177-187
189
I. PENDAHULUAN
Sistem agroforestri tradisional merupakan sistem pertanian yang sudah berumur ratusan tahun dan menjadi model pertanian penting di dunia, terutama di wilayah tropis dan subtropis. Sistem agroforestri tradisional mendatangkan keuntungan secara ekonomi, ekologi, dan sosial budaya bagi
komunitas pengelolanya (Torres, Maza, Aguirre, Hinojosa, & Günter, 2015; Weiwei, Wenhua, Moucheng, & Fuller, 2014). Misalnya, agroforestry berbasis tanaman mangga ( sp) di Mangifera Bangladesh telah menyelamatkan para petani yang minim lahan dari kemiskinan relatif (Rahman, Imam, Snelder, & Sunderland, 2012). Pada komunitas Dayak di Kalimantan dikenal sistem
AGROFORESTRI KALIWU DI SUMBA: SEBUAH TINJAUAN SOSIOLOGIS( )Agroforestry Kaliwu in Sumba: A Sociological Perspective
Budiyanto Dwi PrasetyoBalai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang,
Jalan Alfons Nisnoni Nomor 7B Airnona, Kota Kupang85115, Nusa Tenggara Timur, IndonesiaE-mail: [email protected]
Diterima tgl 4 Mei 2016, direvisi tgl 14 Mei 2016, disetujui tgl 24 November 2016
ABSTRACT
Agroforestry is one of the popular land management systems in Indonesia. The system helps the farmers to increase agricultural production, social life, and ecological stability. Traditional community in Sumba had been implementing agroforestry for a long time, known as Kaliwu and as a part of the indigenous knowledge. Kaliwu as a system is constructed socially through an intensive interaction between local people and its environment and transmitted from generation to generation. This study aimed to asses sociological aspects in behind Kaliwu practices, which allegedly become key factor the sustainability of this system socially, exist until now. The study was conducted for a year in 2009 in the Waimangura Village, Sumba Island. As social research, data was collected through social survey on 30 respondents, in-depth interview, observation, and literature review. Data was analyzed by using quantitative and qualitative procedures. The results indicated that sociologically, Kaliwu as an authentic knowledge of land management system passed on from generation to generation and constructed along with the socio-historical practices by the local people of Sumba. Social norms (adherence to traditional values, arrangement of labour systems, conflict management) and social institution of farmer group became social factors that play significant role to make kaliwu sustainable.
Keywords Agroforestry; traditional; Kaliwu; sociological perspective; Sumba.:
ABSTRAK
Agroforestri merupakan salah satu sistem pengelolaan lahan yang populer di Indonesia terutama di daerah berlahan kritis dan kering. Sistem ini sangat membantu masyarakat desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahannya melalui fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Masyarakat tradisional Sumba mengenal sistem agroforestri dengan nama . Sistem ini telah diterapkan sejak lama dan merupakan bagian dari pengetahuan asli Kaliwumasyarakat Sumba dalam mengelola lahan secara turun temurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek sosiologis di balik praktek yang disinyalir manjadi faktor penentu kelestarian sistem ini dari generasi ke Kaliwugenerasi. Penelitian dilakukan selama setahun pada 2009 di Desa Waimangura, Pulau Sumba. Pengumpulan data dilakukan melalui survei sosial terhadap 30 responden, wawancara, observasi, dan studi pustaka. Data dan informasi yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara sosiologis, Kaliwu merupakan sebuah sistem pengetahuan pengelolaan lahan yang otentik dan terwariskan secara turun-temurun pada masyarakat Sumba. Kaidah-kaidah sosial (ketaatan pada nilai tradisional, pembagian kerja, manajemen konflik) dan lembaga sosial kelompok tani menjadi faktor sosial yang menopang keberlanjutan di tengah masyarakat.Kaliwu
Kata kunci: Agroforestri; tradisional; ; perspektif sosiologis; Sumba.Kaliwu
JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 189-199
190
Tinjauan sosiologis terhadap praktek agroforestri tradisional, seperti halnya , Kaliwumasih belum banyak dibicarakan, sehingga patut dimunculkan pertanyaan: realitas sosiologis seperti apa yang menyebabkan sebuah sistem agroforestri Kaliwu bisa tetap lestari? Tujuan penelitian ini adalah mengkaji realitas sosial yang terkonstruksi secara sosiologis di balik praktek pada Kaliwu masyarakat Sumba. Sasarannya penelitian ini adalah tafsir sosial atas praktek beserta kaliwufaktor-faktor sosial yang menopang keberlanjutan kaliwu pada masyarakat Sumba.
II. METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan selama setahun pada tahun 2009 di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi NTT. Lokasi tersebut dipilih atas pertimbangan banyaknya jumlah sebaran Kaliwu yang dikelola masyarakat, aksesibilitas, dan dinamika sosial masyarakat dalam pengelolaan kaliwu.
B. Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan empat metode pengumpulan data. , metode survei melalui Pertamamewawancarai responden menggunakan kuisioner (Singarimbun & Effendi, 1999). Responden ditentukan secara dengan jumlah sampel purposivesebanyak 30 responden (n = 30). Responden merupakan para petani yang terlibat dalam pengelolaan secara berkelompok. Kaliwu Keduaadalah metode wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilakukan terhadap narasumber kunci ( ), yaitu orang-orang yang memiliki key personpengetahuan mendalam tentang di antara Kaliwu populasi. Mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat (ketua kelompok tani, tokoh agama, dan tokoh adat) dan aparatur desa. , dengan melakukan Ketigametode pencatatan saat observasi di lapangan. Keempat dilakukan pendokumentasian terhadap literatur, baik media ilmiah maupun populer seperti jurnal penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, media internet, dan literatur lainnya juga dilakukan untuk memperkuat tinjauan literatur.
pertanian tradisional berbasis keluarga atau Kalekayang mampu menjaga keanekaragaman hayati sekaligus melestarikan nilai-nilai sosial budaya (Rahu, Hidayat, Ariyadi, & Hakim, 2014). Sistem agroforestri tradisional juga terdapat di daerah lain di Indonesia seperti di Sumatera, Repong DamarSimpunk Kane di Kalimantan, dan atau hutan keluarga di Timor (Kebijakan, 2003).
Di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT), sistem agroforestri tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dikenal dengan istilah atau Kaliwu Kaliwo(Njurumana, GN & Susila, 2006). Seperti sistem-sistem agroforestri pada umumnya, model pengelolaan memiliki manfaat ekologis, Kaliwuekonomis dan sosial. Secara ekologis dapat kaliwumencegah erosi dan meningkatkan cadangan air tanah. Masyarakat memanfaatkan ruang tumbuh vertikal dan horisontal secara optimal dengan melakukan kombinasi tanaman yang beragam (tanaman pertanian, perkebunan, dan kehutanan) (Njurumana, GN & Susila, 2006). Secara ekonomi, hasil yang diperoleh dari tanaman perkebunan dan pangan di dapat memenuhi kebutuhan hidup kaliwusubsiten maupun dijual ke pasar (Njurumana ., et al2009). Secara sosial, ditempatkan sebagai Kaliwu bagian dari proses interaksi sosial di masyarakat dan mengkonstruksi pengetahuan asli masyarakat secara turun-temurun. Hal ini yang membedakan Kaliwu dengan sistem agroforestri modern yang sumber pengetahuannya berasal dari luar masyarakat setempat. Lebih jauh lagi, Kaliwu merupakan media bagi masyarakat Sumba untuk berinteraksi secara sosial, memelihara pengetahuan bercocok-tanam di lahan kering secara tradisional, serta menjamin ketersediaan pangan dan papan. Keberadaan telah menjadi ikon identitas bagi Kaliwu masyarakat Sumba.
Terpeliharanya hingga kini disinyalir Kaliwu karena adanya unsur-unsur sosiologis di dalam masyarakat sebagai pengelolanya. Aspek sosiologis membicarakan struktur sosial dan proses sosial, termasuk di dalamnya mengenai perubahan sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah atau norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial serta lapisan-lapisan sosial (Soemardjan & Soemardi, 1964). Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama (Narwoko & Suyanto, 2006).
Agroforestri Kaliwu di Sumba: Sebuah Budiyanto Dwi Prasetyo ..... ( )
yang diwawancarai mayoritas berumur 25-50 tahun. Sedangkan tingkat pendidikan responden di-dominasi oleh lulusan SMP. Lebih dari setengah responden memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari enam orang. Pekerjaan utama seluruh responden adalah petani. Secara lebih jelasnya karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 1.
2. Kaliwu dan Masyarakat
a. Motif pengelolaan
Sistem Kaliwu di Waimangura memiliki karakteristik spesifik dalam pemilihan lokasi lahan. Hamparan lahan dibentuk dengan susunan pola tata ruang, dimana lokasi Kaliwu yang ditumbuhi tanaman perkebunan berkayu maupun tanaman kehutanan, biasanya diselingi dengan lahan terbuka yang ditanami tanaman pangan seperti jagung, ubi, dan keladi. Lahan terbuka tersebut kemudian disambung lagi oleh Kaliwu milik warga lainnya. Hal itu dilakukan untuk efisiensi kerja sebab Kaliwu dan lahan tanaman pangan letaknya berdekatan. Tujuan lainnya adalah untuk menghindari erosi pada tanah di sekitar kebun Kaliwu atau di lahan tanaman pangan. Erosi diantisipasi dengan membuat terasering menggunakan batu sebagai penahan teras. Bentangan lahan kaliwu secara melintang diilustrasikan dalam Gambar 1.
C. Analisis Data Data dari pengisian kuesioner dianalisis secara
kuantitatif menggunakan statistik deskriptif (Usman & Setiady, 2006) dengan memakai program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Penyaji-an data statistik menggunakan tabel distribusi frekuensi secara tabel silang (Nurgiyantoro, Burhan, & Marzuki, 2004). Analisis kualitatif dilakukan terhadap data hasil observasi, dan in-depth interview,pendokumentasian literatur. Penyajian hasil analisis kualitatif dilakukan secara deskriptif naratif guna melengkapi dan mengonfirmasi data dan informasi secara statistik.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil
1. Karakteristik responden
Responden dalam penelitian ini berjumlah 30 orang terdiri dari 26 laki-laki dan empat perempuan. Penentuan umur responden dilakukan dengan metode yakni dengan memilih purposive samplingresponden yang telah menikah dan berusia di atas 25 tahun. Penentuan kelompok umur responden didasarkan pada usia produktif dan kedewasaan seseorang dalam menyikapi masalah. Responden
191JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 189-199
Tabel 1. Karakteristik responden. Table 1. Charactersistic of respondents
No Pertanyaan (Questions) Jawaban (Answers) Jumlah (Numbers)
1 Jenis kelamin (Sex) Laki-laki (Men) 26 Perempuan (Women)
4
2 Umur (Age) < 25 - 25-50 23 >50
7
3 Pendidikan (Education) Tidak sekolah (Uneducated) 4 SD tamat (Primary school) 10 SLTP tamat (Junior high school) 7 SLTA tamat (Senior high school) 9 Perguruan tinggi (Tertiary school)
-
4 Jumlah keluarga (Family members) < 3 - 3 - 6 11 > 6
19
5 Pekerjaan utama (Main job) Petani (Farmer) 30
Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2009
192Agroforestri Kaliwu di Sumba: Sebuah Budiyanto Dwi Prasetyo ..... ( )
Gambar 1. Bentang lahan kaliwu(Figure 1. The landscape of kaliwu)
Sumber (Source): Njurumana et al., 2009
Tujuan ekonomis (kebutuhan pangan) dan ekologis (penahan erosi) kemudian berkembang menjadi murni komersial. Peningkatan produksi panen yang dihasilkan ternyata mengalami Kaliwu surplus jika sekadar untuk memenuhi kebutuhan subsisten. Surplus terjadi terutama untuk komoditi pangan, kayu pertukangan dan kayu bakar. Diketahui terdapat 56,7% responden menyatakan, alasan mereka mengelola adalah untuk Kaliwu pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan selebihnya dijual ke pasar. Hanya sebagian kecil saja yang mengelola untuk tujuan subsisten dan Kaliwu sebatas kewajiban budaya meneruskan keberadaan Kaliwu.
b. Lahan dan ragam tanaman
Luas keseluruhan lahan, baik lahan kering maupun pekarangan yang dimiliki responden di Desa Waimangura dan dikelola menjadi Kaliwu adalah 43,285 ha dengan luas rata-rata lahan yang dimiliki setiap responden adalah 1,610 ha. Lahan yang dikelola sebagai tersebut terdiri atas Kaliwu tata ruang berupa hamparan lahan terbuka untuk pertanian tanaman pangan di posisi lahan datar dan rendah, serta tanaman perkebunan dan kehutanan untuk lahan yang berada lebih tinggi posisinya dari lahan pertanian tersebut. Luas kepemilikan lahan oleh responden di lokasi penelitian dijelaskan pada Tabel 2.
Tabel . Luas ahan milik esponden Desa Waimangura2 l rTable 2. The number of tenure belong to respondents in Village Waimangura
Lokasi (Location) Luas kepemilikan lahan (Numbers of tenure ) (ha)
Sumba Barat Daya (Southwest Sumba)
Lahan kering (Dry land )
Rata-rata (Approximately )
Lahan pekarangan
(Yard )
Rata-rata (Approximately)
Jumlah lahan kering dan pekarangan
(Dryland & yard in total )
Rata-rata (Approximately)
Waimangura 31,500 1,170 11,785 0,440 43,285 1,610
Sumber ( ): Data primer ( ), 2009Source Primary data
193JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 189-199
Jenis tanaman pangan yang menjadi sumber pangan utama adalah padi dan jagung. Tanaman yang dijadikan cadangan pangan kebanyakan dari jenis ubi dan keladi. Pola konsumsi pangan dan cadangan pangan tersebut sudah berlangsung sejak lama, dimana padi dan jagung menjadi pangan utama sedangkan ubi dan keladi menjadi pendukung pangan utama sebagai sumber cadangan pangan. Komoditas perkebunan yang banyak menghasilkan pendapatan bagi rumah tangga responden adalah jenis buah-buahan seperti pisang, mangga, dan jeruk serta jenis tanaman perkebunan lainnya seperti kopi. Tanaman kehutanan yang menjadi primadona di desa sampel adalah jenis mahoni . Jenis ini (Swietenia mahagony)mampu menghasilkan pendapatan bagi responden dengan nilai yang cukup tinggi.
c. Pembagian kerja
Pengelolaan di Waimangura tidak Kaliwu dikerjakan sendirian oleh kepala keluarga, melainkan dilakukan melalui pembagian kerja secara tradisional dengan melibatkan anggota keluarga. Peran kepala keluarga atau laki-laki usia produktif sangat sentral dalam pengelolaan agroforestri . Kepala keluarga melakukan Kaliwupekerjaan utama bertani mulai dari persiapan lahan hingga pengelolaan pasca panen. Pada kondisi ini, kultur patriarki terlihat sangat dominan di masyarakat Sumba. Kultur ini menempatkan kepala keluarga (laki-laki usia produktif) sebagai orang yang bertanggungjawab atas pemenuhan pangan keluarga melalui sistem . Sistem pembagian Kaliwukerja di dapat dilihat pada Tabel 3.Kaliwu
Kaum perempuan (usia produktif) dan anak-anak tidak dimarginalkan dalam pengelolaan Kaliwu. Para istri justru memainkan peran penting. Mereka umumnya bekerja bertani bersama-sama kepala keluarga (laki-laki) di . Hanya Kaliwusebagian kecil saja istri-istri itu yang menyatakan terlibat hanya pada waktu-waktu tertentu saja dalam bercocok tanam. Lebih jauh lagi, anak-anak berusia kurang dari 14 tahun diketahui juga turut membantu bertani meski proporsinya hanya 40%. Karena sebagian besar anak-anak lainnya, menurut pengakuan responden, sengaja dibebaskan dari pekerjaan bertani dan diprioritaskan untuk bersekolah. Kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan dapat terlihat dari pengakuan narasumber tersebut. Ini sama halnya dengan para lansia yang cenderung dibebaskan dari kegiatan pengelolaan lahan. Pada titik ini, tampak bahwa kegiatan di dalam memprioritaskan tenaga Kaliwu kerja usia produktif di dalam keluarga pengelola.
d. Lembaga-lembaga sosial
Keberadaan mendapat dukungan dari Kaliwu sistem sosial masyarakat desa, terutama lembaga-lembaga sosial baik formal maupun non-formal. Lembaga formal yang mendukung pengelolaan agroforestri tersebut berasal tidak hanya lembaga pemerintahan desa seperti lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), badan permusyawaratan desa (BPD), dan organisasi kepemudaan Karang Taruna, tapi juga lembaga non pemerintah seperti Gereja Kristen Sumba (GKS), dan Kelompok Tani. Lembaga kelompok tani merupakan institusi formal yang paling signifikan perannya dalam menggerakkan masyarakat Waimangura untuk bertani . Kaliwu
Pembagian kerja anggota keluarga (Job descriptions among family members)
Jawaban responden (The answers of respondents)
Kepala Keluarga/
Suami (Husbands)
Istri (Wifes)
Anak-anak (Children)
Lansia (Elderly)
Bertani (Farming) 100% 83,3 % - - Membantu bertani (Help for farming) - 10 % 40 % 6,7% Tidak bertani/tidak ada (Have not taken any role/nothing)
- 6,7 % 60 % 93,3%
Total 100% 100% 100% 100%
Tabel . Sistem pembagian erja dalam engelolaan groforestri di Desa Waimangura3 k p a kaliwuTable 3. Division of labour systems within kaliwu agroforestry management in Village Waimangura
Sumber ( ): Data primer ( ), 2009Source Primary data
194Agroforestri Kaliwu di Sumba: Sebuah Budiyanto Dwi Prasetyo ..... ( )
Peran lembaga pemerintahan desa lebih difungsikan secara politis dan diplomatis. Fungsi politis adalah menjadikan pemerintah desa sebagai sarana untuk menyuarakan kepentingan mereka kepada pemerintah kabupaten/provinsi/pusat dalam kaitannya untuk melestarikan . Fungsi Kaliwudiplomatis adalah sebagai wadah untuk ber-negosiasi dan membuka akses informasi, teknologi, dan jaringan kerjasama dengan pihak luar untuk mendukung pengelolaan Kaliwu.
Peran tokoh agama pun sangat sentral di masyarakat karena suaranya selalu didengar warga karena dirinya adalah panutan masyarakat. Status sosial tokoh agama dalam sistem pelapisan sosial adalah setara dengan tokoh adat. Maka dari itu GKS menjadi lembaga keagamaan yang perannya sangat vital dalam memotivasi warga untuk giat bekerja berdasarkan iman yang mereka percayai. Sebagian anggota GKS diketahui pula menduduki posisi penting dalam struktur lembaga kelompok tani.
Kunci kelestarian di Waimangura ada di Kaliwu kelompok tani. Kelompok tani yang paling aktif dan giat melaksanakan program-programnya adalah . Kata dalam Mawailo Omma Mawailo Ommabahasa Sumba berarti “Marapu petani harus sudah pergi ke kebun sebelum ayam berkokok”. Nama ini mengandung makna filosofis tentang keharusan masyarakat anggotanya memiliki etos kerja yang tinggi. Etos tersebut masih dipelihara dengan baik oleh warga Waimangura. Sebagian warga masih banyak yang pergi bekerja ke lebih dari dua Kaliwu kali dalam sehari. Etos kerja yang tinggi tentunya merupakan modal utama bagi pengembangan agroforestri ke arah yang lebih produktif. Lebih dari itu, kelompok tani juga berfungsi sebagai sarana untuk bersosialisasi, bermusyawarah, meningkat-kan kapasitas keterampilan dan pengetahuan, memobilisasi anggota, serta bekerja sama dengan pihak luar dalam rangka optimalisasi pengelolaan Kaliwu.
Sebaliknya, peran lembaga non formal, yakni lembaga adat diketahui tidak terlalu dominan di Waimangura. Lembaga ini cenderung mengurusi acara-acara seremonial seperti perkawinan dan kematian saja. Peran lembaga adat dalam agroforestri sudah sangat berkurang Kaliwu dikarenakan masuknya agama Kristen Protestan yang diinisiasi GKS. GKS mampu mendominasi konsepsi warga yang tadinya memeluk kepercayaan tradisional Sumba Marapu, menjadi beragama
Protestan. Kondisi seperti itu berdampak pada melemahnya penerapan /larangan terkait pamalipengelolaan lingkungan, termasuk , yang Kaliwudidasarkan pada kepercayaan adat Marapu.
Akan tetapi, melemahnya bukan berarti pamalimenghilangkan sama sekali praktik di pamalikehidupan sehari-hari. yang masih dipegang Pamaliteguh generasi tua penganut Marapu pada kenyataannya tidak berani ditentang generasi pemeluk Protestan. itu berupa larangan Pamalimenebang dan atau membakar pohon besar, terutama yang terdapat di dalam lokasi . KaliwuSebagian besar masyarakat Waimangura masih percaya bahwa melakukan hal tersebut berarti membunuh leluhur mereka sendiri. Di sisi lain, larangan itu sejatinya bertujuan untuk menjaga ekosistem sebagai areal pencegah erosi Kaliwu akibat hempasan hujan serta kekeringan yang dapat merusak lahan sumber pangan mereka.
e. Pengelolaan konflik
Konflik merupakan perosalan yang tidak bisa dihindari dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan, kebun, dan lahan pertanian. Konflik terjadi karena adanya perbedaan cara pandang terhadap sebuah realitas (Gritten, Saastamoinen, & Sajama, 2009). Hal itu disebabkan karena adanya kepentingan dan nilai yang berbeda-beda yang dianut kelompok-kelompok yang berkonflik ketika memaknai realitas tersebut. Pada akhirnya, muncul pemaknaan yang berbeda ter-hadap realitas yang sama. Sebuah versi pemaknaan terhadap realitas biasanya sudah dimanipulasi menurut kepentingan kelompok masing-masing (Gray, 1997 & Moore, 1993 dalam Gritten ., et al2009).
Bentuk konflik menurut Fisher (2001) dalam (Sembiring, Basuni, & Soekmadi, 2010) terdiri atas konflik tertutup ( ), konflik mencuat ( ), latent emergingdan konflik terbuka ( ). Konflik sering manifest latenttidak disadari pihak-pihak yang berselisih karena perselisihan tidak sepenuhnya terangkat ke simpul-simpul konflik. Konflik mencuat ketika ter-identifikasi aktor-aktor yang terlibat dan diakui adanya perselisihan dengan subjek perihal konflik yang jelas namun belum berkembang ke arah pertikaian dan mencari jalan penyelesaian. Konflik manifest adalah jika kedua pihak yang bertikai sudah berselisih secara terang-terangan, sudah melaku-kan kompromi namun mengalami . Konflik deadlock
195JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 189-199
jenis ini kerap memicu terjadinya tindak kekerasan (Fisher 2006 Sembiring ., 2010).dalam et al
Konflik yang terjadi dalam pengelolaan Kaliwu tergolong ke dalam konflik horisontal. Pertikaian yang terjadi atas dua kelompok masyarakat yang berada dalam stuktur sosial yang sama, sebagai warga dan sebagai petani. Persoalan penyerobotan lahan dan pencurian ternak adalah Kaliwu representasi konflik yang paling menonjol. Se angkan untuk intensitas konflik pengelolaan dKaliwu di Desa Waimangura selama tiga tahun (2006-2009) diketahui cukup minim. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh mapannya sistem kelembagaan dan sistem hukum yang diterapkan di desa tersebut. Di sisi lain, meratanya hasil panen pada semua lahan milik warga Kaliwu menjadi indikasi faktor penekan terjadinya konflik.
Lahan merupakan hal terpenting pada masya-rakat petani. Maka dari itu, potensi konflik yang dapat muncul sewaktu-waktu dapat dipastikan ada kaitannya dengan lahan. Namun, pada lahan-lahan Kaliwu di Waimangura, konflik lahan hanya terjadi sekali dalam tiga tahun terakhir, yakni penyerobotan lahan. Hal itupun dapat diselesaikan melalui musyawarah keluarga. Itikad untuk menuntaskan konflik secepatnya merupakan karakteristik masyarakat Desa Waimangura yang tentunya menjadi faktor pendorong bagi stabilitas keamanan desa tersebut. Kemungkinan lainnya adalah karena tingginya etos kerja masyarakat yang tidak gemar menghabiskan waktu untuk bertengkar atau berkelahi.
Pencurian ternak adalah bentuk konflik lainnya yang terjadi lima kali dalam tiga tahun terakhir. Bagi
masyarakat Sumba, ternak seperti kerbau jantan, babi taring, kuda, dan sapi merupakan simbol kekayaan seseorang. Harga ternak bisa melambung hingga puluhan juta per-ekor ketika dipakai untuk keperluan upacara perkawinan atau kematian yang masih berorientasi adat. Maka dari itu, pencurian ternak kerap terjadi di kalangan masyarakat Sumba termasuk di Waimangura. Kondisi itu tentu berpengaruh terhadap pengelolaan lahan , Kaliwudimana seseorang menjadi merasa frustrasi ketika simbol adat dan simbol kekayaannya dicuri. Sejauh ini penyelesaian konflik pencurian ternak tersebut diselesaikan melalui musyawarah keluarga hingga tuntas.
B. Pembahasan
Menafsir secara sosiologis sangat Kaliwu berbeda dari cara perspektif ilmu-ilmu lainnya yang melihat sebagai entitas teknis Kaliwu an-sich yang terlepas dari campur tangan manusia. Perspektif sosiologis menempatkan sebagai Kaliwu sebuah realitas sosial yang merupakan produk dari perjalanan sosio-historis proses sosial di masyarakat dan bergerak membentuk unsur-unsur dari struktur sosial secara dialektis (Hoult, 1969; Soemardjan & Soemardi, 1964; Veeger, 1985). Lebih jauh lagi, seperti dikatakan P.L. Berger (1985), yang terpenting adalah “menelanjangi” realitas sosial dengan tidak hanya mencatat Kaliwu dan menggambarkan realitas sosial yang Kaliwu tampak, melainkan menguak fakta-fakta penting di balik realitas sosial itu sendiri. Skematika Kaliwu tafsir sosiologis atas dapat dilihat pada Kaliwu Gambar 2.
UNSUR-UNSUR SOSIAL 1. Kaidah-kaidah sosial - Nilai tradisional - Pembagian kerja - Manajemen konflik 2. Lembaga-lembaga
sosial
PROSES SOSIAL
PROSES SOSIAL
KALIWU
MASYARAKAT
MASYARAKAT
Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2009
Gambar 2. Skema tafsir sosiologis atas kaliwu.Figure 2. The scheme of social construction of kaliwu
196Agroforestri Kaliwu di Sumba: Sebuah Budiyanto Dwi Prasetyo ..... ( )
Keberadaan Kaliwu dibentuk oleh proses sosial yang menyejarah yang terjadi pada masyarakat Waimangura. Proses sosial itu berjalan akibat adanya interaksi sosial yang intensif baik antar sesama warga masyarakat maupun antara masyarakat dengan ekosistem Kaliwu. Interaksi yang demikian ini (manusia dengan manusia dan manusia-manusia dengan ekosistem Kaliwu), membentuk sebuah konstruksi pola pikir terkait pengelolaan Kaliwu yang terwariskan secara turun-temurun dan kemudian menjadi sebuah penge-tahuan lokal yang sistemik dan orisinil (indigenous knowledge) (Berkes, 2012).
Proses sosial tersebut secara dialektis mem-bentuk unsur-unsur sosial yang tidak lain merupakan pembentuk struktur sosial pada masyarakat itu sendiri. Dalam praktek pengelolaan Kaliwu, menggunakan definisi Soemardjan & Soemardi (1964), unsur-unsur sosial yang nampak dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni kaidah-kaidah sosial dan lembaga-lembaga sosial.
1. Kaidah-kaidah sosial
Masyarakat memiliki kaidah-kaidah atau aturan-aturan sosial yang membuatnya berbeda dari sekumpulan binatang. Kaidah-kaidah sosial itu merupakan seperangkat norma (tertulis maupun tidak tertulis) yang dibentuk dan disepakati bersama untuk menciptakan suatu keteraturan sosial atau social order di masyarakat (Narwoko & Suyanto, 2006). Kaliwu sebagai realitas sosial merupakan sebuah entitas yang tersusun atas kaidah-kaidah sosial tersebut. Terdapat tiga poin penting terkait kaidah-kaidah sosial yang terdapat dalam penge-lolaan Kaliwu.
a) Kaidah nilai tradisionalKetaatan masyarakat terhadap nilai-nilai
tradisional merupakan motivasi utama dalam mengelola Kaliwu. Hal tersebut muncul sebagai bentuk ekspektasi masyarakat terhadap orang tua terutama leluhurnya yang telah mewariskan lahannya untuk dikelola sebagai Kaliwu. Menurut Weber (1957) dalam Abdullah (1985); P. Berger, Parera & Luckman (1990) orang tua dan leluhur merupakan orang-orang berpengaruh (significant others) yang memiliki kharisma dan mampu menciptakan ketaatan masyarakat terhadap nilai-nilai yang hendak dipelihara di dalam masyarakat. Ketaatan terhadap nilai-nilai tradisional dalam
mengelola Kaliwu pada masyarakat Waimangura merupakan keberhasilan internalisasi nilai-nilai tradisional untuk menjaga kelestarian kaliwu yang dilakukan oleh significant others tersebut.
b) Kaidah sistem pembagian kerja Kultur patriarki terlihat sangat dominan di
masyarakat dalam mengelola kaliwu. Kepala keluarga atau laki-laki dewasa diketahui lebih dominan dan bertanggung jawab penuh dalam pemenuhan kebutuhan keluarga dalam bertani Kaliwu. Akan tetapi, uniknya hal tersebut tidak menampik keberadaan perempuan dewasa atau kaum ibu yang juga merasa bertanggung jawab dalam menunjang kegiatan pertanian yang dilakukan laki-laki kepala keluarga. Meski porsi pekerjaan tidak sepenuhnya dibebankan pada kaum ibu, akan tetapi keberadaan mereka sangatlah sentral dalam mengoptimalkan Kaliwu.
Sikap kepedulian kaum ibu muncul bukan karena paksaan, melainkan bentuk dari tanggung jawab gender. Sebab pada kenyataanya, kaum ibu yang membantu bertani di Kaliwu tetap meng-utamakan pekerjaannya untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak. Peran anak-anak yang hanya membantu di Kaliwu pada saat panen dan dalam porsi pekerjaan yang ringan serta dilakukan di luar jam sekolah, merupakan realitas tersendiri yang patut pula diperhatikan. Secara tidak langsung, sistem pembagian kerja yang ada di masyarakat Waimangura dalam mengelola Kaliwu sudah memerhatikan keberadaan anak sebagai manusia yang patut dilindungi hak-haknya dan bukan untuk dieksploitasi.
c) Kaidah pengelolaan konflik.Konflik latent adalah interaksi sosial yang
mengarah pada gesekan-gesekan sosial dalam tensi yang tinggi dan berpotensi menciptakan konflik manifest (Druckman & Fast, 2003; Mitchell, 1981). Intensitas konflik manifest di Desa Waimangura diketahui sangat minim. Lebih dari itu, konflik yang terjadi dengan cepat dapat terselesaikan melalui musyawarah keluarga hingga tuntas. Etos kerja yang tinggi pada masyarakat Desa Waimangura ternyata menjadi salah satu faktor penekan mun-culnya konflik manifest ke permukaan. Masyarakat lebih memilih bekerja di Kaliwu daripada membuang-buang waktu bersengketa atau berkelahi.
197JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 189-199
Namun, potensi konflik cenderung meningkat ketika musim pesta (perkawinan atau kematian). Konflik biasanya dipicu oleh aksi pencurian terhadap hewan ternak seperti babi bertaring, kerbau jantan, dan sapi. Hal ini menjadikan konflik latent sangat berpotensi mencuat menjadi konflik emerging dan lebih jauh lagi menjadi konflik manifest ketika memasuki musim pesta.
2. Lembaga-lembaga sosial
Peran lembaga lembaga-lembaga formal yang ada di lingkup pemerintahan desa, diketahui hanya sekedar menjadi saluran politik masyarakat untuk menyampaikan berbagai ide, gagasan, dan aspirasi yang ingin diwujudkan masyarakat Waimangura untuk menunjang pengelolaan Kaliwu. Namun, lembaga formal tersebut tidak mampu meng-gerakkan masyarakat untuk mengelola Kaliwu secara langsung. Pemerintah desa lebih sering kinerjanya terhalang persoalan birokrasi seperti tidak ada anggaran atau tidak ada instruksi dari birokrat di level lebih tinggi. Maka lembaga pemerintah hanya dijadikan simbol desa secara administratif dan jarang terlibat aktif dalam pengelolaan Kaliwu.
Masyarakat menggunakan inisiatifnya dengan membentuk kelompok tani Mawailo Omma untuk mendukung pengelolaan Kaliwu. Kelompok tani menjadi satu-satunya saluran bagi masyarakat untuk merealisasikan segala ide, gagasan, dan aspirasinya secara praktis dan konkret. Keberadaan kelompok tani telah bergerak lebih jauh dari sekadar urusan Kaliwu, yakni mampu menciptakan jaringan sosial yang bisa menjadi akses untuk berinteraksi dan menciptakan posisi tawar (bargaining position) lembaga itu terhadap lembaga lainnya. Hal itu dapat dilihat dari komposisi pengurus kelompok tani yang ternyata juga berstatus sosial aktif di lembaga pemerintahan desa, lembaga keagamaan (GKS), dan tokoh masyarakat setempat (kepala dusun).
Keberadaan GKS sebagai lembaga keagamaan yang ada di Waimangura diketahui berperan secara signifikan dalam membentuk etos kerja. GKS mampu menciptakan sudut pandang baru di masyarakat, terutama pada generasi muda, bahwa bekerja adalah ibadah, dan berbagai tahyul dan pamali adalah bi'dah. Hal ini senada dengan thesis Max Weber tentang “Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme” (Abdullah, 1979). Meski demikian, masih ditemukan adanya upacara adat Marapu yang digelar oleh generasi tua dan dihadiri jemaat GKS
yang notabene beragama Kristen Protestan. Hal tersebut diakui responden untuk menjaga toleransi dalam berkeyakinan serta menghormati orang tua. Sikap toleransi tersebut merupakan modal sosial dan mampu diterjemahkan secara baik oleh masyarakat Waimangura dalam interaksi ber-masyarakat termasuk dalam pengelolaan kaliwu, misalnya dengan menerapkan sanksi dari hukum-hukum adat Marapu apabila ada pelanggaran yang terjadi di lahan pemilik yang masih memercayai keyakinan Marapu.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dalam perspektif sosiologis, kaliwu tidak hanya dipandang sebagai sebuah entitas teknis berbentuk ekosistem, namun kaliwu dimaknai pula sebagai sebuah realitas sosial yang terbentuk dari proses sosial yang panjang. Proses sosial tersebut melibatkan unsur-unsur sosial yang merupakan dasar pembentuk struktur sosial di masyarakat. Kaidah nilai tradisional, sistem pembagian kerja, dan manajemen konflik serta lembaga pemerin-tahan desa, kelompok tani, dan lembaga agama merupakan unsur-unsur sosial yang menonjol dan berkontribusi besar terhadap keberlanjutan Kaliwu hingga saat ini.
B. Saran
Dalam melakukan penyusunan kebijakan dan program-program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di masyarakat sebaiknya tidak hanya melihat aspek teknis seperti ekologi dan biofisik saja, namun turut pula menempatkan aspek sosiologis di dalamnya. Untuk melestarikan dan mengarus-utamakan sistem Kaliwu di tempat lain, perlu dilakukan inisiasi pencanangan desa model Kaliwu oleh stakeholders terkait.
UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepala Desa dan warga Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi NTT, yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.
198Agroforestri Kaliwu di Sumba: Sebuah Budiyanto Dwi Prasetyo ..... ( )
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, T. (Eds.). (1979). Agama, etos kerja dan perkembangan ekonomi. Jakarta: LP3ES.
Abdullah, T. (1985). . Sejarah lokal di IndonesiaYogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Berger, P. L. (1985). . Jakarta: Inti Humanisme sosiologiAksara.
Berger, P., Parera, F., & Luckman, T. (1990). Tafsir sosial atas kenyataan: risalah tentang sosiologi pengetahuan (terj: Hasan Basri). Jakarta: LP3ES.
Berkes, F. (2012). Sacred ecology: traditional ecological knowledge and management systems. London: Taylor & Francis. Retrieved 1 Agustus 2015. https://books.google.co.id/books?id=5b8RAgZtxxIC&printsec=frontcover&dq=sacred+ecology&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjRqJvPp9rRAhVMqI8KHY9DDekQ6AEIKjAB#v=onepage&q=sacred%20ecology&f=false.
Druckman, D., & Fast, L. (2003). Conflict: From analysis to intervention. In Cheldelin, S, Druckman, D., & Fast, L (Eds.). London-New York: Continuum. Retrieved 24 April 2 0 1 5 f r o m https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=y5LUAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Conflict+Analysis+Intervention+Sandra+Cheldelin&ots=Tk8p5CMHNo&sig=eQ5rapLc1EHCUWGMqrYT8vaHV3Aredir_esc=y#v=onepage&q=Conflict%20Analysis%20Intervention%20Sandra%20Cheldielin&f=false.
Gritten, D., Saastamoinen, O., & Sajama, S. (2009). Ethical analysis: A structured approach to facilitate the resolution of forest conflicts. Forest Policy and Economics, 11(8), 555-560. h t t p : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 1 6 / j.forpol.2009.07.003.
Hoult, T. F. (1969). . The Dictionary of modern sociologyUnviersity of Michigan: Littlefield Adams.
Kebijakan, W. (2003). . Bogor: Perhutanan socialCenter for International Forestry Research (CIFOR).
Mitchell, C. R. (1981). The structure of international conflict (pp. 251-272) London: MacMillan Press Ltd.
Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2006). Sosiologi teks pengantar dan terapan. In Narwoko, J. D., & Suyanto, B (Eds.), Sosiologi teks pengantar dan terapan (pp. 74-96). Jakarta: Penerbit Kencana.
Njurumana, G. N., & Susila, I. (2006). Kajian rehabilitasi lahan kritis melalui pengem-bangan hutan rakyat berbasis sistem kaliwu di Pulau Sumba. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam, 3(1), 473-484.
Njurumana, G., Raharjo, S., Pujiono, E., Prasetyo, B. Rianawati, H., & Puspiyatun, R. (2009). Pengembangan agroforestry berbasis masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan (Laporan Penelitian: Program Insentif Riset untuk Peneliti). Kupang: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional (Unpublished).
Nurgiyantoro, Burhan, G., & Marzuki. (2004). Statistik terapan untuk penelitian ilmu-ilmu sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Rahman, S. A., Imam, M. H., Snelder, D. J., & Sunderland, T. (2012). Agroforestry for livelihood security in agrarian landscapes of the Padma floodplain in Bangladesh. Small-scale Forestry, 11(4), 529-538. http://doi.org/ 10.1007/s11842-012-9198-y.
Rahu, A. A., Hidayat, K., Ariyadi, M., & Hakim, L. (2014). Management of Kaleka (traditional gardens) in Dayak community in Kapuas, Central Kalimantan. International Journal of Science and Research, 3(3), 205-210.
Sembiring, E., Basuni, S., & Soekmadi, R. (2010). Resolusi konflik pengelolaan Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Kabupaten Teluk Wondama, Jurnal Manajemen Hutan Tropika, XVI 2(2), 84-91.
Singarimbun, M., & Effendi, S. (Eds.). (1999). Metode penelitian survey. Jakarta: LP3ES.
Soemardjan, S., & Soemardi, S. (1964). Setangkai bung sosiologi. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Torres, B., Maza, O. J., Aguirre, P., Hijojosa, L., & Günter, S. (2015). The contribution of traditional agroforestry to climate change adaptation in the Ecuadorian Amazon: The chakra system. In Handbook of Climate Change Adaptation (pp. 1973-1994). Verlag Berlin Heidelberg: Springer. http://doi.org/ 10.1007/978-3-642-38670-1_90.
Usman, H., & Setiady, P. (2006). . Pengantar statistikaJakarta: Bumi Aksara.
Veeger, K. (1985). . Jakarta: Gramedia.Realitas sosial
Weiwei, L., Wenhua, L., Moucheng, L., & Fuller, A. M. (2014). Traditional agroforestry systems: One type of globally important agricultural heritage systems. Journal of Resources and E c o l o g y , 5 ( 4 ) , 3 0 6 - 3 1 3 . http://doi.org/10.5814/j . issn.1674-764x.2014.04.004.
199JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 3 Desember 2016, Hal. 189-199
INDEKS SUBJEK
A K Air 47 Kelompok tani 1 Agroforestry 73, 189 kelembagaan 1 Analisis stakeholder 121 Kapulaga 25 Analisis manfaat biaya 135 Konservasi 37 Kearifan lokal 63 B Kesediaan membayar 155 Burung dilindungi 37 Kelayakan 85 Biochar 135 Kerja sama 121 Katingan 165 D Kenyamanan udara 177 Daur optimal 145 Kota Bogor 177 Kaliwu 189 G Gmelina 145 M H Masyarakat Bali 63 Hutan rakyat 1,25 Hutan desa 85 N Hulu DAS Ciliwung 121 Nuri talaud 37 Harga optimal 155 NPV 145 I P Implementasi 85 Penyuluhan 25 Iklim mikro 177 Pulau Karakelang 37 Pengelolaan hutan bambu 63 J Pengembangan kelembagaan 73 Jawa Barat 25 Peubah akses 107 Jasa lingkungan 47 Perilaku para pihak 107 Jawa Tengah 73 Peran 121 Jaminan alam 107 Proyek karbon 145 Penggunaan lahan 165 Penataan ruang 165 Preferensi stakeholder 165 Perspektif sosiologis 189 R V Redd+ 165 Valuasi ekonomi 47 S W Strategi 85 Wisata alam Bantimurung 155 Sekam padi 135 Willingnes to pay 177 Sumba 189 T TN Babul 47 Tumbuhan obat 107 Tradisional 189
INDEKS PENGARANG A L Abd Kadir Wakka 47 Leti Sundawati 85 Agus Poerwadianto 107 Latifah Kosim Kadarusman 107 Andry Saputra 177 B M Budiman Achmad 25 M Zahrul Muttaqin 121 Budiyanto Dwi Prasetyo 189 Maria Magdalena Diana Widiastuti 135 D N Dian Diniyati 25 Nurheni Wijayanto 85 Diah Irawati Dwi Arini 37 Nugroho Adi Utomo 165 Dhani Yuniati 63 R Desmantoro 85 Raden Mohamad Mulyadin 13 Dodik Ridho Nurrochmat 107 Retno Maryani 121 Dudung Darusman 177 Ricky Avenzora 177 Rachmad Hermawan 177 E Elvida Yosefi Suryandari 121 S Surati 13 H Satria Astana 145 Hardjanto 1, 107 Santun RP Sitorus 165 Husnul Khotimah 63 W I Wahyudi Isnan 155 Indah Bangsawan 1 Isdomo Yuliantoro 37 Y Irma Yeni 63 Yulius Hero 1 Idin Saepudin Ruhimat 73 Yongki Indrajaya 145Ignatius Adi Nugroho 107 Iis Alviya 121 K Kuncoro Ariawan 13
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI KEHUTANAN
Vol.13 No.1
DINAMIKA KELOMPOK TANI DAN PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTENIndah bangsawan, Hardjanto, Yulius Hero
KAJIAN HUTAN KEMASYARAKATAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN: KASUS DI KAB. GUNUNG KIDULRaden Mohammad Mulyadin, Surati, Kuncoro Ariawan
PENGARUH PENYULUHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KAPULAGA DI HUTAN RAKYAT: KASUS DI KABUPATEN CIAMIS DAN TASIKMALAYA, JAWA BARATDian Diniyati, Budiman Achmad
TIPOLOGI DAN MOTIVASI MASYARAKAT PEMELIHARA NURI TALAUD SEBAGAI BURUNG DILINDUNGI DI PULAU KARAKELANGDiah Irawati Dwi Arini, Isdomo Yuliantoro
VALUASI EKONOMI MANFAAT AIR DI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG, SULAWESI SELATANNur Hayati, Abd Kadir Wakka
KEARIFAN LOKAL DAN PRAKTIK PENGELOLAAN HUTAN BAMBU PADA MASYARAKAT BALIIrma yeny, Dhani Yuniati, Husnul Khotimah
Vol.13 No.2
FAKTOR KUNCI DALAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN AGROFORESTRY PADA LAHAN MASYARAKATIdin Saepudin Ruhimat
KELAYAKAN PROGRAM HUTAN DESA DI DESA TANJUNG AUR II KECAMATAN PINO RAYA KABUPATEN BENGKULU SELATANDesmantoro, Nurheni Wijayanto, Leti Sundawati
PERILAKU EKONOMI PARA PIHAK DALAM PEMANFAATAN TUMBUHAN OBAT DI TN MERU BETIRI JAWA TIMURIgnatius Adi Nugroho, Dodik Ridho Nurrochmat, Hardjanto, Latifah Kosim Kadarusman, Agus Poerwadianto
MENINGKATKAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN WILAYAH HULU DAERAH ALIRAN SUNGAI CILIWUNGIis Alviya, Elvida Yosefi Suryandari, Retno Maryani, Zahrul Muttaqin
ANALISIS MANFAAT BIAYA BIOCHAR DI LAHAN PERTANIAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI DI KABUPATEN MERAUKEMaria Magdalena Diana Widiastuti
1-12
13-23
25-36
37-46
47-61
63-72
73-84
85-106
107-120
121-134
135-143
Vol.13 No.3
DAUR OPTIMAL TEGAKAN GMELINA PADA DUA PROYEK KARBON: MEMPERPANJANG DAUR DAN AFORESTASIYonky Indrajaya & Satria Astana
HARGA OPTIMALTIKET MASUK WISATA ALAM BANTIMURUNG, SULAWESI SELATANWahyudi Isnan
SINERGI TATA RUANG TERHADAP PELAKSANAAN REDD+: STUDI KASUS DI KABUPATEN KATINGAN, KALIMANTAN TENGAHNugroho Adi Utomo & Santun R. P. Sitorus
ORIENTASI MASYARAKAT KOTA BOGOR TERHADAP NILAI KENYAMANAN UDARAAndry Saputra , Ricky Avenzora , Dudung Darusman, & Rachmad Hermawan
AGROFORESTRI KALIWU DI SUMBA: SEBUAH TINJAUAN SOSIOLOGISBudiyanto Dwi Prasetyo
145-154
155-163
165-176
177-187
189-199
JUDUL (Times New Roman, all caps, 14 pt, bold, centered)Title (Times New Roman, 12 pt, italic, bold, centered)
(kosong dua spasi tunggal, 12 pt)
Penulis Pertama , Penulis Kedua dan Penulis Ketiga1 2 3(Times New Roman, 10 pt, , centered1Nama Jurusan, Nama Fakultas, Nama Universitas, Alamat, Kota, Kode Pos, Negara;
e-mail: [email protected] Lembaga Penelitian, Alamat, Kota, Kode Pos, Negara;
e-mail: [email protected] Lembaga Penelitian, Alamat, Kota, Kode Pos, Negara;
e-mail: [email protected](kosong dua spasi tunggal, 12 pt)
Diterima ……, direvisi ……, disetujui …… (diisi oleh Sekretariat)
ABSTRACT (12 pt, bold, italic)(kosong satu spasi tunggal, 12 pt)
Abstract should be written in Indonesian and English using Times New Roman font, size 10 pt, italic, single space.. Abstract is not a merger of several paragraphs, but it is a full and complete summary that describe content of the paper It should contain background, objective, methods, results, and conclusion from the research. It should not contain any references nor display mathematical equations. It consists of one paragraph and should be no more than 200 words in bahasa Indonesia and in English(kosong satu spasi tunggal 10 pt).
Keywords: 3 - 5 keywords (Times New Roman, 10 pt)(kosong satu spasi tunggal 10 pt)
ABSTRAK (12 pt, bold)(kosong satu spasi 12 pt)
Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan jenis huruf Times New Roman, ukuran 10 pt, italic, spasi tunggal. Abstrak bukanlah penggabungan beberapa paragraf, tetapi merupakan ringkasan yang utuh dan lengkap yang menggambarkan isi tulisan. Sebaiknya abstrak mencakup latar belakang, tujuan, metode, hasil, serta kesimpulan dari penelitian. Abstrak tidak berisi acuan atau tidak menampilkan persamaan matematika, dan singkatan yang tidak umum. Abstrak terdiri dari satu paragraf dengan jumlah kata paling banyak 200 kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.(kosong satu spasi tunggal 10 pt)
Kata kunci: 3 - 5 kata kunci (Times New Roman, 10 pt)(kosong enam spasi tunggal, 10 pt)
(TimesNew
Roman,10 pt,
centered)
PETUNJUK UNTUK PENULIS (Guide for Authors)Petunjuk penulisan ini dibuat untuk keseragaman
format penulisan dan kemudahan bagi penulis dalam proses penerbitan naskah di Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan. Penulis dapat menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Naskah dalam bahasa Indonesia harus sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) yang berlaku, dan bila dalam bahasa Inggris sebaiknya memenuhi standar tata bahasa Inggris baku.
Naskah ditulis dalam format kertas berukuran A4 (210 mm x 297 mm) dengan margin atas 3 cm, margin bawah 3 cm, margin kiri dan kanan masing–masing 2 cm. Bentuk naskah berupa 2 kolom dengan jarak antar kolom 1 cm. Panjang naskah hendaknya maksimal 12 halaman, termasuk lampiran. Jarak antara paragraf adalah satu spasi tunggal. Naskah merupakan hasil penelitian dalam bidang sosial dan ekonomi kehutanan, serta lingkungan. Naskah harus berisi informasi yang benar, jelas dan memiliki kontribusi substantif terhadap bidang kajian.
FORMAT: Naskah diketik di atas kertas putih A4, Times New Roman, font 12, keculai Abstrak, Kata Kunci dan Daftar Pustaka font 10.
SISTEMATIKA PENULISANJUDULIdentitas PenulisABSTRAK & Kata KunciI. PENDAHULUANII. METODE PENELITIANIII. HASIL DAN PEMBAHASANIV. KESIMPULAN DAN SARANUCAPAN TERIMA KASIH(ACKNOWLEDGMENT)DAFTAR PUSTAKALAMPIRAN
Tubuh naskah diatur dalam Bab dan Sub bab secara konsisten sesuai dengan kebutuhan. Semua nomor ditulis rata di batas kiri tulisan, seperti:I, II, III, dst. untuk BabA, B, C, dst. untuk Sub Bab1, 2, 3, dst. untuk Sub Sub Baba, b, c, dst. untuk Sub Sub Sub Bab1), 2), 3), dst. untuk Sub Sub Sub Sub Baba), b), c), dst. untuk Sub Sub Sub Sub Sub Bab
JUDUL: Dibuat dalam 2 bahasa, harus mencerminkan isi tulisan, dan ditulis dengan Times New Roman. Bahasa Indonesia dengan font 14, huruf kapital, tegak dan tidak lebih dari 2 baris atau tidak lebih dari 13 kata. Bahasa Inggris dengan font 12, huruf kecil, italik, dan diapit tanda kurung. Judul naskah harus mencerminkan inti dari isi suatu tulisan. Judul hendaknya akurat, singkat, padat, informatif, mudah diingat dan mudah dipahami. Menggambarkan isi pokok tulisan. Mengandung kata kunci yang menunjukkan isi tulisan. Judul seringkali digunakan dalam sistem pencarian informasi. Hindari pemakaian kata kerja. Hindari pemakaian rumus kimia, rumus matematika, bahasa singkatan dan tidak resmi.
IDENTITAS PENULIS: Nama penulis (tanpa gelar dan jabatan) dicantumkan di bawah judul, di bawahnya diikuti nama dan alamat instansi, no. telp./faks. serta alamat e-mail penulis ditulis dengan font lebih kecil dari font teks (font 10). Bila penulis lebih dari satu, penulisan nama berurutan mulai penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga dan seterusnya sesuai dengan peran dan sumbangan yang diberikan serta tanggungjawab yang dibebankan.
ABSTRAK: Dibuat dalam dua bentuk: pertama untuk Lembar Abstrak, maksimal 100 kata, dan kedua (Abstrak) maksimal 200 kata, keduanya berupa intisari dari naskah secara menyeluruh dan informatif. Kedua abstrak tersebut dibuat dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Abstrak merupakan pernyataan singkat, berupa intisari secara menyeluruh mengenai permasalahan, tujuan, metodologi dan hasil yang dicapai. Ditempatkan sebelum pendahuluan; diketik dengan jarak satu spasi. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak ada gambar, tabel dan pustaka. Tidak mencantumkan istilah yang kurang dimengerti, akronim atau singkatan, nama atau merek dagang atau tanda lain tanpa keterangan. Dapat merangsang pembaca untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Naskah dalam bahasa Indonesia: disajikan abstract (bahasa Inggris) yang dicetak miring, disusul abstrak (bahasa Indonesia) yang dicetak tegak. Naskah dalam bahasa Inggris: berlaku sebaliknya.
KATA KUNCI: Dicantumkan di bawah abstrak masing-masing, maksimal 5 entri, dibuat dalam bahasa yang digunakan dalam Lembar Abstrak dan Abstrak.
I. PENDAHULUAN (12 pt, bold)(kosong satu spasi tunggal, 10 pt)
Pendahuluan mencakup hal–hal berikut ini: , berisi uraian permasalahan dan Latar belakangalasan pentingnya masalah tersebut diteliti. Permasalahan diumuskan secara jelas, penjelasan ditekankan pada rencana pemecahan masalah dan keterkaitannya dengan pencapaian luaran yang telah ditetapkan. , berisi pernyataan secara Tujuanjelas dan singkat tentang hasil yang ingin dicapai dari serangkaian kegiatan penelitian yang akan dilakukan. atau menjelaskan secara Sasaran luaranspesifik yang merupakan hasil antara dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Hasil yang telah dicapai, dijelaskan kaitannya dengan kegiatan yang dilaksanakan (khusus untuk kegiatan penelitian lanjutan).
II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan harus ditulis sesuai dengan cara ilmiah, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Mengemukakan semua bahan yang digunakan seperti tumbuhan kayu, bahan kimia, alat dan lokasi penelitian. Tanaman dan binatang ditulis lengkap dengan nama ilmiah. Menggunakan tolok ukur internasional, system matrix dan standar nomenklatur. Metode penelitian dijelaskan sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Pelaksanaan penelitian disusun berurutan menurut waktu, ukuran dan kepentingan. Jika metode merupakan kutipan harus dicantumkan dalam referensi. Jika dilakukan perubahan terhadap metode kutipan atau standar harus disebutkan perubahannya. Bila diperlukan dapat disajikan dalam tabel. Metode statistik (bila ada) harus disebutkan dengan singkat.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil disajikan dalam bentuk uraian umum. Disusun secara berurutan sesuai dengan tujuan penelitian. Jika tujuan penelitian tidak tercapai perlu dikemukakan alasan dan penyebabnya, agar peneliti lain tidak mengulanginnya. Tabulasi, grafik, analisis statistik dilengkapi dengan tafsiran yang benar. Judul, keterangan tabel dan gambar dilengkapi dengan terjemahan bahasa Inggris dengan huruf miring; atau sebaliknya. Angka yang tercantum dalam tabel tidak perlu diuraikan lagi, tetapi cukup dikemukakan makna atau tafsiran masalah yang diteliti; dalam bagian ini juga dapat disajikan ilustrasi dalam bentuk grafik bagan, pictogram dan sebagainya. Dapat mengemukakan perbandingan hasil yang berlainan dan beberapa perlakuan. Metode statistik yang digunakan dalam pengolahan data harus dikemukakan, sehingga tingkat kebenaran dapat ditelusuri. Prinsip dasar metode harus diterangkan dengan mengacu pada referensi atau keterangan lain mengenai masalah ini. Penulis mengemukakan pendapatnya secara objektif dengan dilengkapi data kuantitatif.
Pembahasan dapat menjawab apa arti hasil yang dicapai dan apa implikasinya. Dapat menafsirkan hasil dan menjabarkannya, sehingga dapat dimengerti pembaca. Mengemukakan hubungan dengan hasil penelitian sebelumnya. Bila berbeda tunjukkan, bahas dan jelaskan penyebab perbedaan tersebut. Hasil penelitian ditafsirkan dan dihubungkan dengan hipotesis dan tujuan penelitian. Mengemukakan fakta yang ditemukan dan alasan mengapa hal tersebut terjadi.
Menje l a skan kema juan pene l i t i an dan kemungkinan pengembangan selanjutnya.
Simbol/lambang ditulis dengan jelas dan konsisten. Istilah asing ditulis dengan huruf . italicSingkatan harus dituliskan secara lengkap pada saat disebutkan pertama kali, setelah itu dapat ditulis kata singkatnya.
TABEL: Diberi nomor, judul, dan keterangan yang diperlukan, ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Tabel ditulis dengan Times New Roman ukuran 10 pt dan berjarak satu spasi di bawah judul tabel. Judul tabel ditulis dengan huruf berukuran 10 pt, rata kiri, dan ditempatkan di atas tabel. Penomoran tabel menggunakan angka Arab (1, 2, …..). Tabel diletakkan segera setelah disebutkan di dalam naskah. Tabel diletakkan pada posisi paling atas atau paling bawah dari setiap halaman. Apabila tabel memiliki lajur/kolom cukup banyak, dapat digunakan format satu kolom atau satu halaman penuh. Apabila judul pada lajur tabel terlalu panjang, maka lajur diberi nomor dan keterangannya di bawah tabel. Sumber ( ) Sourceditulis di kiri bawah tabel.
(kosong satu spasi tunggal, 10 pt)Tabel 1. Perkembangan luas hutan rakyat di 10 kabupaten
terluas dalam pembangunan hutan rakyat di Jawa Tengah
Table 1. Community forests areas development in 10 largest regencies in community forest establishment in Central Java
(kosong satu spasi tunggal, 10 pt)
Sumber ( ): Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Source(2013a).
(kosong satu spasi tunggal, 10 pt)
GAMBAR: Gambar, grafik, dan ilustrasi lain yang berupa gambar harus berwarna kontras (hitam putih atau berwarna), masing-masing harus diberi nomor, judul, dan keterangan yang jelas dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Gambar diletakkan segera setelah disebutkan dalam naskah. Gambar diletakkan pada posisi paling atas atau paling bawah dari setiap halaman. Gambar
diletakkan simetris dalam kolom. Apabila gambar cukup besar, bisa digunakan format satu kolom. Penomoran gambar menggunakan angka Arab. Penulisan keterangan gambar menggunakan huruf Times New Roman pt, center berukuran 10 , dan diletakkan di bagian bawah, seperti pada contoh di atas. Sumber ( ) ditulis di kiri bawah gambar.Source
Sumber ( ): Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Source(2013a).
(kosong satu spasi tunggal, 10 pt)
Gambar 1. Persentase luas hutan rakyat di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011.
Figure 1. Area percentage of community forests in Central Java Province in 2011.
(kosong dua spasi tunggal, 10 pt)
FOTO: Harus mempunyai ketajaman yang baik, diberi nomor, judul, dan keterangan yang jelas dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Resolusi gambar disarankan paling sedikit 300 dpi, sehingga gambar tetap terbaca jelas meskipun diperbesar.
Apabila terdapat persamaan reaksi atau matematis, diletakkan simetris pada kolom. Nomor persamaan diletakkan di ujung kanan dalam tanda kurung, dan penomoran dilakukan secara berurutan. Apabila terdapat rangkaian persamaan yang lebih dari satu baris, maka penulisan nomor diletakkan pada baris terakhir. Penunjukan persamaan dalam naskah dalam bentuk singkatan, seperti persamaan (1).
(kosong satu spasi tunggal 11 pt)
(1)
(kosong satu spasi tunggal 11 pt)
Penurunan persamaan matematis tidak perlu ditulis semuanya secara detail, hanya dituliskan bagian yang terpenting, metode yang digunakan dan hasil akhirnya.
No.Kabupaten
(Regency) Tahun (Year) (ha)
2005 2006 2007 1 Wonogiri 25.100 25.643 36.359 2 Kendal 12.407 12.724 12.737 3 Banjarnegara 13.154 15.610 19.290 4 Purbalingga
13.027
14.117
14.143
5 Purworejo
20.771
23.186
20.567 6 Wonosobo
19.824
20.687
19.619
7 Pati
15.762
16.049
16.049 8 Banyumas
13.204
14.963
17.090
9 Boyolali
9.392
9.758
7.950 10 Sragen
17.064
17.220
18.049
Kabupaten lainnya
15.735
175.866
184.776
Jumlah (Total) 317.440 345.823 366.629
ka
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. KesimpulanKesimpulan memuat hasil yang telah
dibahas. Hal yang perlu diperhatikan adalah segitiga konsistensi (masalah-tujuan-kesimpulan harus konsisten).
B. SaranSaran dapat dikemukakan untuk dipertim-
bangkan pembaca.
UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)
Merupakan bagian yang wajib ada dalam sistematika karya tulis ilmiah. Suatu penelitian tidak akan berhasil tanpa melibatkan pihak-pihak yang telah membantu, baik berperan secara finansial, teknis, maupun substantif. Ucapan terima kasih merupakan sebuah kewajiban, bukan pilihan (opsional).
Pengutipan pustaka di dalam naskah berdasarkan sistem penulisan referensi APA Style, sebagai berikut:
· Karya dengan dua pengarang. Research by Wegener and Petty (1994) supports... atau (Wegener & Petty, 1994)
· Karya tiga sampai lima pengarang.(Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993) atau Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow (1993) explain….Dalam kutipan berikutnya, (Kernis ., 1993) atau Kernis et alet al. (1993) argued….
· Enam pengarang atau lebih.Harris . (2001) argued... atau (Harris ., 2001) et al et al
· Pengarang tidak diketahui, sitasi sumber pada judul dengan huruf miring. Sitasi sumber pada judul buku atau laporan dengan huruf miring, contoh: …berdasarkan Statistik daerah Kabupaten Pesawaran 2013 ……. Sedangkan pada judul artikel, bab, dan halaman web dalam tanda kutip dan dilengkapi tahun, contoh : A similar study was done of students learning to format research papers ("Using APA," 2001).
· Organisasi sebagai pengarang. According to the American Psychological Association (2000),... atau menggunakan singkatan jika telah dikenal dalam tanda bracket pertamakali sumber dikutip dan selanjutnya hanya singkatan yang disitasi. Sitasi pertama: (Mothers Against Drunk Driving [MADD], 2000) Sitasi kedua: (MADD, 2000).
· Dua karya atau lebih dalam tanda kurung yang sama (Berndt, 2002; Harlow, 1983)
· Pengarang dengan nama akhir sama.Gunakan inisial nama pertama dan nama terakhir, (E. Johnson, 2001; L. Johnson, 1998)
· Dua karya atau lebih dengan pengarang sama dalam tahun sama. Research by Berndt (1981a) illustrated that...
· Mensitasi/mengutip sumber tidak langsung. Johnson argued that...(as cited in Smith, 2003, p. 102).
· Tahun tidak diketahui. Another study of students and research decisions discovered that students succeeded with tutoring ("Tutoring and APA," n.d.).
DAFTAR PUSTAKA(kosong satu spasi tunggal, 10 pt)
Daftar pustaka merupakan referensi yang dirujuk dalam naskah, diutamakan terbitan paling lama 5 tahun terakhir. Format penulisan Daftar Pustaka mengacu pada American Psychological Association (APA) style. Referensi terdiri dari acuan primer dan/atau acuan sekunder. Sumber acuan primer adalah sumber acuan yang langsung merujuk pada bidang ilmiah tertentu, sesuai topik penelitian dan sudah teruji. Sumber acuan primer dapat berupa: tulisan dalam makalah ilmiah dalam jurnal internasional maupun nasional terakreditasi, hasil penelitian di dalam disertasi, tesis, maupun skripsi. Buku ( ), termasuk dalam sumber textbookacuan sekunder. Semua karya yang dikutip dalam penulisan karya tulis harus dimuat dalam daftar pustaka (dan sebaliknya).
Daftar pustaka pada halaman terpisah dari uraian penulisan. Ukuran margin seperti pada halaman penulisan. Judul daftar pustaka berada di tengah dan tidak dicetak miring/tanda kutip. Kapitalkan hanya huruf pertama pada kata pertama dan pada judul. Jarak antar karya proper noun(pustaka) dua spasi. Inden pada baris kedua dengan jarak ½ inch. Daftar pustaka harus disusun berdasarkan .alphabet
Penulisan sitasi dan daftar pustaka diharuskan menggunakan aplikasi referensi seperti Mendeley, Endnote.
LAMPIRAN
Contoh Penulisan Daftar Pustaka Berdasarkan APA Style:
Paper dalam jurnala. Artikel dalam jurnal ilmiah dengan volume dan nomor (1
penulis).Williams, J.H. (2008). Employee engagement: Improving
participation in safety. (12), 40-Professional Safety, 5345.
b. Artikel dalam jurnal ilmiah dengan volume dan nomor (2-6 penulis). Astana, S., Soenarno, & Karyono, O.K. (2014). Implikasi
perubahan tarif dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan terhadap laba pemegang konsesi hutan dan penerimaan negara bukan pajak: Studi kasus hutan alam produksi di Kalimantan Timur, Indonesia. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 11(3), 251- 264.
c. Artikel dalam jurnal ilmiah dengan volume dan nomor (lebih dari 6 penulis). Reed, M.S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H.,
Hubaek, K., Morris, J., … Stringer, L.C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. Journal of Environmental Management, 2009(90), 16.
Bukua. Buku (1 penulis).
Alexie, S. (1992). The business of fancydancing: Stories and poems. Brooklyn, NY: Hang Loose Press.
b. Buku (2-6 penulis). Saputro, G.B., Hartini, S., Sukardjo, S., Susanto, A., &
Poniman, A. (2009). . Peta mangroves IndonesiaJakarta: Pusat Survei Sumber Daya Alam Laut, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional.
c. Buku (lebih dari 6 penulis). Atmosoedardjo, H.K., Kartasubrata, J., Kaomini, M.,
Saleh, W., … & Moerdoko, W. (2000). Sutera Alam Indonesia. Jakarta: Penerbit Yayasan Sarana Wana Jaya.
ProsidingKuntadi, & Adalina, Y. (2010). Potensi sebagai Acacia mangium
sumber pakan lebah madu (pp. 915-921). Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia (MAPEKI) XIII: Pengembangan ilmu dan teknologi kayu untuk mendukung implementasi program perubahan iklim, Bali 10-11 Nopember 2010. Bogor: Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia.
Kumpulan tulisan yang dieditBooth-LaForce, C., & Kerns, K.A. (2009). Child-parent
attachment relationships, peer relationships, and peer-group functioning. In K.H. Rubin, W.M. Bukowski, & B. Laursen (Eds.), Handbook of peerinteractions, relationships, and groups (pp. 490-507). New York, NY: Guilford Press.
Makalah seminar, lokakaryaIbnu, S. (2011, Maret). . Makalah Isi dan format jurnal ilmiah
disajikan dalam Lokakarya Nasional Pengelolaan dan Penyuntingan Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Negeri Malang.
Skripsi, disertasi, tesisSuyana, A. (2003). Dampak penjarangan terhadap struktur dan riap
tegakan di hutan produksi alami PT. Inhutani I Berau Kalimantan Timur (Tesis Pascasarjana). Universitas Mulawarman, Samarinda.
Laporan PenelitianSidiyasa, K., Mukhlisi, & Muslim, T. (2010). Jenis-jenis tumbuhan
hutan asli Kalimantan yang berpotensi sebagai sumber pangan dan aspek konservasinya (Laporan Hasil Penelitian). Samboja: Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Samboja (unpublished).
Artikel dari internet:Ahira, A. (2011). Adaptasi morfologi dari paruh burung kolibri.
Diunduh 7 Juni 2012 dari http://www.anneahira.com/ paruh-burung-kolibri-h.tm cache.
Kenney, G.M., Cook, A., & Pelletier, J. (2009). Prospects for reducing uninsured rates among children: How much can premium assistance programs help? Retrieved 7 June 2012 from Urban I n s t i t u t e we b s i t e : h t t p : / / w w w. u r b a n . o r g / url.cfm?ID=411823.
Surat kabarBooth, W. (1990, October 29). Monkeying with language: Is
chimp using words or merely aping handpers? The Washington Post. p.A3.
Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dan sejenisnyaPeraturan Daerah No. 11 tahun 2013 tentang RTRW Kota
Medan 2011-2031.
Peraturan Walikota Medan No. 10 tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
CATATAN: Penggunaan titik dan koma dalam penulisan angka: Naskah (teks) bahasa Indonesia: titik (.) menunjukkan kelipatan ribuan dan koma (,) menunjukkan pecahan. Naskah (teks) bahasa Inggris: titik (.) menunjukkan pecahan dan koma (,) menunjukkan kelipatan ribuan.
KONDISI: Dewan Redaksi berhak mengubah naskah tanpa mengurangi isi yang terkandung di dalamnya, dan juga berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan. Penulis dari luar instansi Badan Litbang Kehutanan wajib menyertakan curriculum vitae singkat dan alamat yang jelas.
PENGAJUAN NASKAH
1. Redaksi Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan menerima naskah ilmiah berupa hasil penelitian dalam bidang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Kehutanan. Naskah harus berisi informasi yang benar, jelas dan memiliki kontribusi substantif terhadap bidang kajian.
2. Penulisan harus singkat dan jelas sesuai dengan format penulisan Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan. Naskah belum pernah dimuat atau tidak sedang dalam proses untuk dimuat di media lain, baik media cetak maupun elektronik.
3. Naskah ilmiah yang masuk akan diseleksi oleh Dewan Redaksi yang memiliki wewenang penuh untuk mengoreksi, mengembalikan untuk diperbaiki, atau menolak tulisan yang masuk meja redaksi bila dirasa perlu. Penilaian secara substantif akan dilakukan oleh Mitra Bestari/ Penyunting Ahli. Penilaian akan dilakukan secara obyektif dan tertulis.
4. Naskah ilmiah yang dimuat dalam Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan tidak berarti mencerminkan pandangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI).
5. Informasi mengenai penerbitan Jurnal Peneliti-an Sosial dan Ekonomi Kehutanan dapat diakses di website www.puspijak.org.http://