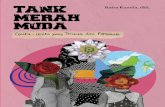Efek-antipiretik-air-rebusan-daun-sirih-merah-Piper-crocatum ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Efek-antipiretik-air-rebusan-daun-sirih-merah-Piper-crocatum ...
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
EFEK ANTIPIRETIK AIR REBUSAN DAUN SIRIH MERAH
(Piper crocatum RP) PADA TIKUS PUTIH
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran
Haris Agung Nugroho
G0006088
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Surakarta
2010
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
PENGESAHAN SKRIPSI
Skripsi dengan judul: Efek Antipiretik Air Rebusan Daun Sirih Merah
(Piper crocatum RP) pada Tikus Putih
Haris Agung Nugroho, NIM/Semester: G0006088/IX, Tahun: 2010
Telah diuji dan sudah disahkan di hadapan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada Hari Senin, Tanggal 1 Nopember 2010
Surakarta,………………………
Pembimbing Utama
Nama : Nur Hafidha Hikmayani, dr., M.Clin.Epid
NIP : 19761225 200501 2 001
Pembimbing Pendamping
Nama : Yul Mariyah, Dra., Apt., M.Si
NIP : 19510329 198303 2 001
Penguji Utama
Nama : Endang Sri Hardjanti, dr., P.FarK
NIP : 19471007 197611 2 001
Anggota Penguji
Nama : H. Zainal Abidin, dr., M.Kes
NIP : 19460202 197610 1 001
.................................
.................................
.................................
.................................
Ketua Tim Skripsi
Muthmainah, dr., M.Kes
NIP : 19660702 199802 2 001
Dekan Fakultas Kedokteran UNS
Prof. Dr. A.A. Subijanto, dr., MS
NIP : 19481107 197310 1 003
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
PERNYATAAN
Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pandapat yang pernah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Surakarta, Oktober 2010
Haris Agung Nugroho
NIM. G0006088
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
ABSTRAK
Haris Agung Nugroho, G0006088, 2010. Efek Antipiretik Air Rebusan Daun
Sirih Merah (Piper crocatum RP) pada Tikus Putih, Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antipiretik air rebusan
daun sirih merah (Piper crocatum RP) pada tikus putih yang diinduksi demam
menggunakan vaksin DPT.
Metode: Subjek berupa 25 ekor tikus putih jantan dengan berat ±200g dan berusia
±2 bulan. Tikus dibagi menjadi 5 kelompok sama besar, yaitu kelompok kontrol
negatif (2ml akuabides), kontrol positif (9mg/200gBB asetaminofen), air rebusan
daun sirih merah dosis 1 (2g/200gBB), dosis 2 (4g/200gBB), dan dosis 3
(6g/200gBB). Pengukuran suhu dilakukan sebelum pemberian vaksin DPT, 2 jam
setelah pemberian vaksin DPT, dan 30’ sekali setelah perlakuan sampai menit ke-
120. Data penelitian dianalisis dengan uji anova repeated measures.
Hasil: Hasil uji anova repeated measures menunjukkan tidak adanya perbedaan
yang bermakna (p>0.05) pada subjek antarwaktu pengukuran sedangkan pada
subjek antarkelompok perlakuan terdapat perbedaan yang bermakna (p<0.05).
Hasil uji post hoc menunjukkan bahwa perbedaan yang bermakna (p<0.05)
terdapat antara kelompok kontrol positif dengan kelompok dosis 1, sedangkan
antara kelompok kontrol positif dengan kelompok dosis 2 dan dosis 3 tidak
terdapat perbedaan yang bermakna (p>0.05).
Simpulan: Air rebusan daun sirih merah (Piper crocatum RP) mempunyai efek
antipiretik pada tikus putih.
Kata kunci: Air rebusan daun sirih merah, antipiretik, Piper crocatum RP.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
ABSTRACT
Haris Agung Nugroho, G0006088, 2010. Antipyretic Effect of Water Decoction
of Red Betel Leaf (Piper crocatum RP) on White Rats, Medical Faculty of
Sebelas Maret University.
Objective: The objective of this study is to evaluate the antipyretic effect of water
decoction of red betel leaf (Piper crocatum RP) on white rats induced fever using
DPT vaccine.
Methods: This was an experimental study using pre and post test with control
group design. Twenty five white male rats with weight ±200g and ±2 months old
were divided into five groups, namely negative control group (2ml aquabidest),
positive control group (acetaminophen 9mg/200gBW), first dose group of water
decoction of red betel leaf (2g/200gBW), second dose group (4g/200gBW) and
third dose group (6g/200gBW). The temperature was measured before and 2 hours
after induced by DPT vaccine, and every 30 minutes post treatment until 120
minutes. Data were analyzed with repeated measures ANOVA test.
Result: The results of repeated measures ANOVA test showed no significant
difference (p>0.05) among temperature measurements over time, but there was a
significant difference (p<0.05) among the five groups. The result of post hoc test
analysis showed that the significant difference (p<0.05) was between positive
control group and dose 1 group. No significant differences (p>0.05) were found
between positive control group and both dose 2 and dose 3 group.
Conclusion: The water decoction of red betel leaf (Piper crocatum RP) has an
antipyretic effect on white rats.
Keywords: Water decoction of red betel leaf, antipyretic, Piper crocatum RP.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
PRAKATA
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan
rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efek
Antipiretik Air Rebusan Daun Sirih Merah (Piper crocatum RP) pada Tikus
Putih”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat
kelulusan tingkat sarjana S1 Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan
kesulitan. Namun berkat bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh semua
pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Prof. Dr. A. A. Subijanto, dr., MS selaku Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Muthmainah, dr., M.Kes selaku Ketua Tim Skripsi Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Nur Hafidha Hikmayani, dr., M.Clin.Epid selaku Pembimbing Utama atas
semua bimbingan, saran, dan masukan dalam penyusunan skripsi.
4. Yul Mariyah, Dra., Apt., M.Si selaku Pembimbing Pendamping atas semua
bimbingan, saran, dan masukan dalam penyusunan skripsi.
5. Endang Sri Hardjanti, dr., P.FarK selaku Penguji Utama atas semua
bimbingan, saran, dan masukan dalam penyusunan skripsi.
6. H. Zainal Abidin, dr., M.Kes selaku Anggota Penguji atas semua
bimbingan, saran, dan masukan dalam penyusunan skripsi.
7. Tim Skripsi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret yang telah
memberikan pelayanan dan kemudahan dalam pelaksanaan skripsi.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran di
masa yang akan datang.
Surakarta, Nopember 2010
Haris Agung Nugroho
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
DAFTAR ISI
PRAKATA ................................................................................................... vi
DAFTAR ISI ................................................................................................ vii
DAFTAR GAMBAR .................................................................................... ix
DAFTAR TABEL ........................................................................................ x
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1
B. Rumusan Masalah ......................................................................... 3
C. Tujuan Penelitian .......................................................................... 3
D. Manfaat Penelitian ........................................................................ 3
BAB II LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka .......................................................................... 4
1. Sirih Merah .............................................................................. 4
2. Demam .................................................................................... 8
3. Antipiretik ............................................................................... 15
4. Vaksin DPT ............................................................................. 18
B. Kerangka Pemikiran ..................................................................... 20
C. Hipotesis ....................................................................................... 21
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian ............................................................................. 22
B. Lokasi Penelitian .......................................................................... 22
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
C. Subjek Penelitian .......................................................................... 22
D. Teknik Sampling .......................................................................... 22
E. Variabel Penelitian ........................................................................ 23
F. Skala Pengukuran Variabel............................................................ 23
G. Definisi Operasional ..................................................................... 24
H. Rancangan Penelitian.................................................................... 25
I. Alat dan Bahan Penelitian ............................................................. 26
J. Cara Kerja...................................................................................... 27
K. Analisis Data ................................................................................ 30
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Data Hasil Penelitian .................................................................... 31
B. Analisis Hasil................................................................................ 33
BAB V PEMBAHASAN .............................................................................. 37
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan ...................................................................................... 41
B. Saran ............................................................................................ 41
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 42
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Struktur Kimia Flavonoid .......................................................... 6
Gambar 2. Pemasukan dan Pengeluaran Panas ............................................ 10
Gambar 3. Ringkasan Patofisiologi Demam................................................ 12
Gambar 4. Ringkasan Biosintesis Prostaglandin ......................................... 14
Gambar 5. Asetaminofen ............................................................................ 17
Gambar 6. Grafik Rerata Hasil Pengukuran Suhu pada Setiap Kelompok ... 32
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Rerata Hasil Pengukuran Suhu Rektal Tikus ................................... 31
Tabel 2. Hasil Uji T Berpasangan dan Uji Wilcoxon Signed Rank Suhu Awal
dan Suhu Setelah Induksi................................................................ 34
Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Anova Repeated Measures Perbandingan Efek
Antipiretik pada Subjek antar Waktu Pengukuran dan Subjek antar
Kelompok....................................................................................... 34
Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji Post Hoc Perbandingan Efek Antipiretik ........ 35
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Hasil Pengukuran Suhu Rektal Tikus
Lampiran 2. Hasil Uji Kruskal-Wallis Pengukuran Suhu Awal
Lampiran 3. Hasil Uji T Berpasangan dan Uji Wilcoxon Signed Rank
Lampiran 4. Hasil Uji ANOVA Repeated Measures
Lampiran 5. Foto-foto Penelitian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia sekarang ini mulai
menggalakkan penggunaan obat tradisional. Obat tradisional merupakan
bahan atau ramuan bahan yang berasal dari bahan alam seperti tumbuh-
tumbuhan yang dimanfaatkan untuk mengobati berbagai penyakit dan
digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat (Hargono, 1992). Obat
tradisional memiliki beberapa keunggulan, salah satunya adalah efek samping
yang lebih ringan jika dibanding obat sintetik. Selain itu, obat tradisional juga
dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat karena harganya relatif lebih
murah (Afdhal, 1996). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang
manfaat dan efek negatif obat tradisional sehingga penggunaannya dapat
dipertanggungjawabkan secara medis.
Salah satu penyakit atau gejala penyakit yang seringkali diobati dengan
pengobatan tradisional adalah demam (Wijayakusuma, 1995). Demam
merupakan suatu gejala penyakit yang sering terjadi. Pemanfaatan obat
tradisional sebagai penurun demam tidak terlepas dari kandungan zat di
dalamnya yang bersifat antipiretik. Flavonoid merupakan salah satu zat yang
banyak terdapat dalam tanaman dan bersifat antipiretik (Singh et al., 2000).
Tanaman yang mengandung flavonoid seperti tanaman sambiloto (Setoaji,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
2004) dan brotowali (Ernitawati, 2004) terbukti memiliki efek antipiretik dan
dapat digunakan sebagai obat antipiretik tradisional.
Sirih merah (Piper crocatum RP) merupakan salah satu tanaman obat
yang daunnya banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional (Sudewo, 2005).
Penggunaan daun sirih merah sebagai obat tradisional berhubungan erat
dengan kandungan zat aktif yang dimiliki. Daun sirih merah terbukti
mengandung flavonoid (Safithri dan Fahma, 2005; Manoi, 2007). Dengan
kandungan flavonoid tersebut, daun sirih merah (Piper crocatum RP)
berpotensi sebagai obat alami penurun demam (antipiretik).
Bentuk rebusan merupakan sediaan obat tradisional yang dikonsumsi
sebagai air minum. Bentuk rebusan merupakan cara yang sering dipakai
masyarakat karena cara ini cepat dan mudah digunakan. Rebusan dibuat dalam
jumlah secukupnya dan tidak memerlukan pengemasan (Masniari et al.,
2006).
Asetaminofen (parasetamol) merupakan salah satu obat antipiretik yang
banyak digunakan oleh masyarakat dan dijual bebas (Tjay dan Rahardja,
2002). Sebagai antipiretik, asetaminofen bekerja dengan menghambat enzim
siklooksigenase. Fungsi ini diperankan oleh gugus aminobenzen yang
merupakan gugus aktif asetaminofen (Wilmana dan Gan, 2007). Flavonoid
sebagai antipiretik juga bekerja seperti asetaminofen dengan menghambat
enzim siklooksigenase (Sitompul, 2003). Penghambatan enzim
siklooksigenase menyebabkan turunnya produksi prostaglandin sehingga set
point suhu tubuh kembali normal (Sherwood, 2001; Guyton, 2007).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
Berdasarkan keterangan di atas, peneliti mencoba melakukan penelitian
untuk mengetahui efek antipiretik air rebusan daun sirih merah (Piper
crocatum RP) pada tikus putih yang diinduksi demam menggunakan vaksin
DPT.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah
penelitian ini yaitu:
”Apakah air rebusan daun sirih merah (Piper crocatum RP) mempunyai efek
antipiretik pada tikus putih?”
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya efek antipiretik
air rebusan daun sirih merah (Piper crocatum RP) pada tikus putih.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mengenai
manfaat daun sirih merah (Piper crocatum RP).
2. Manfaat praktis
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian
berikutnya untuk pengembangan potensi daun sirih merah (Piper crocatum
RP) sebagai antipiretik alternatif.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka
1. Sirih Merah (Piper crocatum RP)
a. Taksonomi
Klasifikasi sirih merah menurut Backer dan Brink (1963) adalah
sebagai berikut:
Kingdom : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Ordo : Piperales
Famili : Piperaceae
Genus : Piper
Spesies : Piper crocatum Ruiz & Pav
b. Sinonim
Piper betle Var. Rubrum
c. Deskripsi dan Morfologi
Tanaman sirih merah tumbuh merambat dengan batang
berbentuk bulat berwarna hijau keunguan. Daun sirih merah berbentuk
menyerupai jantung hati dengan bagian ujungnya meruncing dan
bertangkai. Permukaan daun sirih merah mengkilap dan tidak merata.
Perbedaan sirih merah dengan sirih hijau adalah selain daunnya yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
berwarna merah keperakan, bila daun sirih merah disobek maka akan
mengeluarkan lendir dan aromanya lebih wangi. Tanaman sirih merah
menyukai tempat teduh, berhawa sejuk dengan sinar matahari 60-
75%. Sirih merah dapat tumbuh subur dan baik di daerah pegunungan.
Bila tumbuh di daerah panas, batangnya akan cepat mengering dan
warna merah daunnya akan pudar (Manoi, 2007).
Sirih merah dapat diperbanyak dengan cara vegetatif melalui
penyetekan atau pencangkokan karena tanaman ini tidak berbunga.
Sirih merah dapat beradaptasi dengan baik di setiap jenis tanah dan
tidak terlalu sulit dalam pemeliharaannya. Selama ini umumnya sirih
merah tumbuh tanpa pemupukan. Hal terpenting yang harus
diperhatikan selama pertumbuhannya adalah pengairan yang baik dan
cahaya matahari yang diterima sebesar 60 - 75% (Manoi, 2007).
d. Kandungan Kimia
Dalam daun sirih merah terkandung senyawa fitokimia yakni
alkaloid, saponin, tanin dan flavonoid (Safithri dan Fahma, 2005;
Manoi, 2007). Alkaloid memiliki khasiat sebagai antibakteri dengan
cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada dinding sel
bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan
menyebabkan kematian sel (Robinson, 1999). Tanin juga memiliki
aktivitas antibakteri melalui kemampuannya merusak membran sel
bakteri (Akiyama et al., 2001). Sedangkan flavonoid banyak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
dihubungkan dengan aktivitasnya sebagai analgesik, antiinflamasi dan
antipiretik (Mutalik et al., 2003; Venkatesh et al., 2003).
Flavonoid merupakan senyawa fenol terbesar yang ditemukan di
alam. Senyawa ini merupakan zat warna merah, ungu, biru, dan kuning
yang ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan. Flavonoid larut dalam air
dan cukup stabil dalam pemanasan yang mencapai suhu 100˚C
(Harborne, 1996). Senyawa flavonoid terdiri dari beberapa jenis
tergantung pada tingkat oksidasi dari rantai propana dari sistem 1,3-
diarilpropana yang merupakan struktur dasar flavonoid. Flavonoid
secara garis besar dikelompokkan menjadi empat golongan utama
yaitu flavones, flavanone, catechins, dan anthocyanins (Nijveldt et al.,
2001).
Gambar 1. Struktur Kimia Flavonoid (Nijveldt et al., 2001)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
Sebagian besar senyawa flavonoid ditemukan di alam dalam
bentuk glikosida dengan unit flavonoidnya terikat pada suatu gula.
Glikosida merupakan kombinasi gula dan alkohol yang saling
berikatan melalui ikatan glikosida (Nijveldt et al., 2001).
Flavonoid sebagai antipiretik bekerja seperti aminobenzen yaitu
dengan menghambat enzim siklooksigenase yang berperan dalam
metabolisme asam arakidonat menjadi prostaglandin (Sitompul, 2003).
Penghambatan enzim siklooksigenase akan menurunkan produksi
prostaglandin sehingga set point termostat tubuh di hipotalamus
diturunkan kembali dan demam dapat turun (Sherwood, 2001; Guyton,
2007).
e. Manfaat
Daun sirih merah memiliki manfaat yang cukup banyak.
Beberapa manfaat daun sirih merah adalah sebagai antiinflamasi,
antiseptik, antioksidan, dan antidiabetes (Manoi, 2007).
Dengan kandungan flavonoid, daun sirih merah juga diharapkan
mampu menunjukkan khasiatnya sebagai antipiretik. Beberapa
penelitian menunjukkan bahwa tanaman yang mengandung flavonoid
seperti tanaman sambiloto (Setoaji, 2004), brotowali (Ernitawati,
2004), semak bunga putih (Owoyele et.al., 2008), dan bayam duri
(Kumar et.al., 2009) memiliki efek antipiretik. Penelitian Hastuti
(2007) juga menunjukkan bahwa daun sirih (Piper betle L.) memiliki
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
efek antipiretik. Tanaman sirih (Piper betle L.) memiliki genus sama
dengan sirih merah (Piper crocatum RP) yaitu genus Piper.
2. Demam
a. Definisi
Demam diartikan sebagai peningkatan suhu inti tubuh yang
melebihi normal, meliputi tiga fase klinis yaitu fase dingin (chill), fase
demam (fever), dan fase kemerahan (flush). Fase dingin merupakan
fase dimana terjadi kenaikan suhu tubuh menuju set point yang baru.
Fase demam terjadi ketika suhu tubuh sudah mencapai set point baru
dan tercapai keseimbangan antara produksi dan pengeluaran panas.
Sedangkan fase kemerahan terjadi ketika set point suhu tubuh kembali
ke normal, ditandai dengan berkeringat dan kulit kemerahan karena
vasodilatasi pembuluh darah (Dalal dan Zhukovsky, 2006). Suhu tubuh
normal berkisar antara 36,5˚-37,2˚C sehingga demam pada umumnya
terjadi pada kenaikan suhu di atas 37,2˚C (Nelwan, 2006).
Thompson (2005) telah menganalisis dan mengidentifikasi poin
penting tentang konsep demam yaitu :
1) Demam merupakan respon yang terkoordinasi akibat adanya
stimulus imun (biologis maupun kimiawi).
2) Demam merupakan proses adaptif sebagai respon fase akut yang
melibatkan sistem otonom, tingkah laku, dan neuroendokrin.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
3) Pada demam terjadi peningkatkan set point termostat tubuh di
hipotalamus. Termoregulasi masih berlangsung selama demam dan
demam termasuk self-limiting.
4) Kenaikan suhu merupakan tanda utama demam, dimana
kenaikannya melebihi 1˚C di atas suhu tubuh harian normal. Tidak
ada patokan suhu absolut untuk mendefinisikan demam.
5) Perubahan set point suhu tubuh dipertahankan dengan penyimpanan
dan pembentukan panas tubuh sampai agen penginduksi demam
hilang dari tubuh.
b. Patofisiologi
Suhu tubuh manusia dipertahankan dalam keadaan normal
dengan menjaga keseimbangan antara produksi dan pengeluaran panas
tubuh (Sherwood, 2001; Dalal dan Zhukovsky, 2006; Guyton, 2007).
Pengaturan suhu tubuh ini dilakukan melalui mekanisme umpan balik
yang diatur oleh pusat pengaturan suhu yang terdapat di hipotalamus
(Guyton, 2007). Neuron-neuron pada hipotalamus anterior preoptik
dan hipotalamus posterior menerima dua jenis sinyal, pertama dari
saraf perifer yang mencerminkan reseptor-reseptor untuk hangat dan
dingin dan yang kedua dari temperatur darah yang membasahi daerah
ini. Kedua sinyal ini diintegrasikan oleh pusat termoregulasi
hipotalamus untuk mempertahankan temperatur normal (Gelfand,
2005).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
Konsep terpenting dari pengaturan suhu tubuh adalah
keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran panas. Pemasukan
panas terjadi melalui produksi panas internal (terutama dari aktivitas
otot dan laju metabolisme) dan penambahan panas dari lingkungan
eksternal. Sementara pengeluaran panas terjadi melalui pengurangan
panas dari permukaan tubuh ke lingkungan eksternal dengan cara
radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi (Sherwood, 2001). Alur
termoregulasi tubuh diperlihatkan dalam Gambar 2.
Gambar 2. Pemasukan dan Pengeluaran Panas (Sherwood, 2001)
Demam merupakan reaksi fisiologis yang kompleks sebagai
respon terhadap suatu penyakit. Reaksi demam ini melibatkan sitokin
yang memerantarai terjadinya kenaikan suhu tubuh, membangkitkan
reaksi fase akut, mengaktifasi sistem imun dan endokrin (Mackowiak
et al., 1997). Sitokin-sitokin tersebut kebanyakan merupakan produk
dari sel-sel mononuklear dan sering disebut sebagai sitokin pirogen.
Produksi
panas internal
Pemasukan
panas
Pengeluaran
panas
Lingkungan
eksternal
Suhu inti
tubuh
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
Beberapa di antara sitokin tersebut adalah interleukin-1 (IL-1),
interleukin-6 (IL-6), dan faktor nekrosis tumor α (TNF α). Sitokin
pirogen yang terbentuk kemudian menuju ke sirkulasi darah di daerah
hipotalamus dan akan meningkatkan ekspresi dari enzim
siklooksigenase-2 (COX-2). Ekspresi COX-2 ini akan memacu
peningkatan kadar prostaglandin terutama prostaglandin E2.
Prostaglandin tersebut akan mengaktifkan neuron-neuron
termoregulasi di hipotalamus anterior sehingga set point termoregulasi
tubuh naik (Gelfand, 2005).
Pengaturan suhu tubuh (termoregulasi) pada demam tetap
berlangsung, tetapi dengan patokan (set point) yang lebih tinggi
(Brunton et al., 1996; Sherwood, 2001; Thompson, 2005). Ketika set
point termoregulasi menjadi lebih tinggi, semua mekanisme untuk
meningkatkan suhu tubuh terlibat untuk menyesuaikan dengan set
point baru tersebut. Mekanisme tersebut dilakukan dengan
meningkatkan penyimpanan dan pembentukan panas, termasuk di
dalamnya dengan mengaktivasi sistem saraf simpatis. Aktivasi sistem
saraf simpatis akan menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah kulit,
menghambat aktivitas kelenjar keringat, dan mengaktivasi pusat
menggigil di hipotalamus, sehingga produksi panas meningkat
(Sherwood, 2001). Ringkasan patofisiologi demam disajikan dalam
Gambar 3.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
Keterangan :
: menghambat
Gambar 3. Ringkasan Patofisiologi Demam (Dalal dan Zhukovsky, 2006)
Pirogen eksogen
(agen infeksius,
toksin, tumor)
Fagosit
mononuklear
Sitokin pirogen (IL-1, faktor nekrosis
tumor, interferon gamma, IL-6)
Hipotalamus anterior
Pertahanan panas
(vasokonstriksi,
tingkah laku)
Produksi panas
(kontraksi otot
involunter)
Demam
Antipiretik
k
AINS
Set point
termoregulasi
PGE2
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
Prostaglandin, leukotrien, dan molekul sejenisnya sering disebut
sebagai eicosanoid karena kebanyakan memiliki 20 karbon (eicosa-)
dalam molekulnya. Kebanyakan prostaglandin disintesis dari asam
arakidonat. Prostaglandin ini disebut dengan prostaglandin “series 2”
karena kebanyakan dari mereka mempunyai 2 rantai ganda (Murakami
dan Kudo, 2004).
Proses biosintesis prostaglandin melibatkan dua macam kontrol.
Kontrol pertama yaitu pelepasan asam lemak, dalam hal ini asam
arakidonat, dari membran fosfolipid. Kontrol pertama ini melibatkan
enzim fosfolipase A2 yang berfungsi mengkonversi fosfolipid menjadi
asam arakidonat. Kontrol kedua dalam biosintesis prostaglandin
disebut dengan lintasan siklooksigenase (COX). Enzim utama dalam
lintasan ini adalah enzim siklooksigenase (COX). Lintasan
siklooksigenase memiliki dua aktivitas yaitu oksigenase dan
peroksidase. Aktivitas oksigenase berperan mengubah asam arakidonat
menjadi prostaglandin G2 sedangkan aktivitas peroksidase berperan
mengkonversi prostaglandin G2 tersebut menjadi prostaglandin H2.
Selanjutnya, prostaglandin H2 melalui aktivitas prostaglandin sintase
dan tromboksan sintase, akan diubah menjadi prostaglandin D2,
prostaglandin E2, prostaglandin F2, prostasiklin, dan tromboksan A2
(Murakami dan Kudo, 2004). Ringkasan biosintesis prostaglandin
tersaji dalam Gambar 4.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
Keterangan :
: menghambat
Gambar 4. Ringkasan Biosintesis Prostaglandin (Murakami dan Kudo, 2004)
Asam Arakidonat
Membran fosfolipid
Prostaglandin G2
Prostaglandin H2
Prostaglandin
F2
Prostaglandin
E2
Prostaglandin
D2
Prostasiklin
(PGI2)
Tromboksan
(TXA2)
Peroksidase
PG sintase
Siklooksigenase
(COX) 1/2
Fosfolipase A2
AINS
Kortikosteroid
Tromboksan
sintase
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
3. Antipiretik
Antipiretik merupakan obat yang dapat menekan atau mengurangi
peningkatan temperatur tubuh yang tidak normal (Brunton, 1996; Ganong,
2005). Obat antipiretik sangat sering digunakan oleh masyarakat. Hal ini
dikarenakan bahwa demam merupakan gejala penyakit yang sering terjadi.
Demam merupakan salah satu tanda penyakit infeksi yang angka
kejadiaannya di Indonesia masih tergolong tinggi (Notosiswoyo et al.,
1998).
Hampir semua obat analgesik perifer (non opioid) bersifat
antipiretik. Oleh sebab itu, istilah analgesik-antipiretik sering dipakai
sebagai satu kesatuan. Obat analgesik-antipiretik bekerja dengan
menghambat enzim siklooksigenase (COX) yang berperan dalam
biosintesis prostaglandin (Tjay dan Rahardja, 2002).
Enzim siklooksigenase merupakan enzim yang berfungsi mengubah
asam arakidonat menjadi prostaglandin. Enzim siklooksigenase memiliki
dua isoform, yaitu enzim siklooksigenase-1 (COX-1) dan enzim
siklooksigenase-2 (COX-2). Kedua enzim tersebut mengkatalisis reaksi
dan menghasilkan produk yang sama, yaitu prostaglandin, tetapi dengan
fungsi biologis yang berbeda. COX-1 diekspresikan pada hampir semua
jaringan dan bertanggungjawab menghasilkan prostaglandin yang berperan
dalam menjaga homeostatis pada saluran pencernaan, aliran darah ginjal,
dan sistem vaskuler, sedangkan ekspresi COX-2 diinduksi oleh stimulan
seperti inflamasi atau mitogenik. COX-2 bertanggungjawab pada
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
biosintesis prostaglandin yang terlibat pada reaksi inflamasi, demam, dan
rasa nyeri (Schror dan Kirchrath, 2000).
Sebagian besar obat AINS yang beredar saat ini masih bersifat non-
selektif COX, sehingga selain menghambat COX-2 juga menghambat
COX-1. Penghambatan COX-1 inilah yang memunculkan efek samping
pada penggunaan obat AINS, utamanya pada saluran gastrointestinal.
COX-1 yang terdapat pada saluran gastrointestinal berfungsi memproduksi
prostaglandin yang berperan menjaga aliran darah di lapisan mukosa.
Penghambatan fungsi COX-1 tersebut akan mengganggu aliran darah pada
mukosa lambung dan menyebabkan iskemia mukosa lambung yang dapat
berlanjut menjadi ulkus (Dubois et al., 1998).
Obat analgesik-antipiretik dikelompokkan menjadi beberapa
golongan yaitu:
a. Golongan paraaminofenol
Preparat golongan paraaminofenol yang terpenting dan paling
banyak digunakan adalah asetaminofen atau parasetamol (Gambar 5).
Asetaminofen adalah metabolit dari fenasetin, yang dahulu banyak
digunakan sebagai analgesik, tetapi kemudian ditarik dari peredaran
karena bersifat nefrotoksik dan karsinogenik. Asetaminofen
mempunyai khasiat analgesik-antipiretik, tetapi efek antiinflamasinya
sangat lemah. Asetaminofen dianggap sebagai obat analgesik-
antipiretik yang paling aman dan dijual bebas untuk swamedikasi
karena jarang menimbulkan efek samping. Asetaminofen dapat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
digunakan oleh ibu hamil dan menyusui. Absorbsi asetaminofen di
usus bersifat cepat dan tuntas sementara secara rektal lebih lambat.
Penggunaan asetaminofen dalam jangka panjang dapat menyebabkan
nefropati analgesik (Tjay dan Rahardja, 2002).
Gambar 5. Asetaminofen (Katzung dan Payan, 1998)
Sebagai antipiretik, asetaminofen bekerja dengan menurunkan set
point suhu tubuh dengan menginhibisi enzim siklooksigenase (COX)
yang berperan dalam sintesis prostaglandin E2 (Wilmana dan Gan,
2007). Asetaminofen memiliki selektivitas penghambatan enzim
siklooksigenase pada sistem nervus sentral dan memiliki efek yang
lemah pada saluran gastrointestinal sehingga asetaminofen jarang
menimbulkan efek samping pada lambung (Lucas, 2005).
b. Golongan asam salisilat
Preparat golongan salisilat contohnya adalah aspirin (asetosal)
yang merupakan prototip dan obat standar kelompok antiinflamasi
non-steroid (AINS). Secara sistemik, aspirin digunakan sebagai
analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan antigout. Penggunaan aspirin
secara lokal sebagai keratolitik dan counter iritant. Efek samping
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
penggunaan aspirin yang sering adalah iritasi lambung dan reaksi
alergi (Wilmana dan Gan, 2007).
c. Golongan pirazolon
Preparat golongan pirazolon yang umum digunakan adalah
dipiron (antalgin). Dipiron digunakan hanya sebagai analgesik-
antipiretik karena efek antiinflamasinya lemah. Penggunaan dipiron
dapat menimbulkan efek samping berupa agranulositosis, anemia
aplastik, dan trombositopenia (Wilmana dan Gan, 2007).
d. Golongan AINS lainnya
Obat antiinflamasi non steroid (AINS) lainnya yang cukup sering
digunakan adalah asam mefenamat, diklofenak, dan ibuprofen. Asam
mefenamat adalah derivat dari asam fenamat. Penggunaan asam
mefenamat sering menimbulkan efek samping berupa iritasi lambung.
Diklofenak merupakan derivat asam fenilasetat sedangkan ibuprofen
adalah derivat asam propionat. Diklofenak dan ibuprofen tidak
dianjurkan untuk wanita hamil (Wilmana dan Gan, 2007).
4. Vaksin DPT (Difteri, Pertusis, dan Tetanus)
Vaksin difteri terbuat dari toksin kuman difteri yang dilemahkan
(toksoid). Vaksin difteri biasanya diolah dan dikemas bersama-sama
dengan vaksin tetanus dalam bentuk vaksin DT, atau dengan vaksin
tetanus dan pertusis dalam bentuk vaksin DPT. Reaksi imunisasi yang
mungkin terjadi adalah demam ringan, pembengkakan dan rasa nyeri di
tempat suntikan selama 1-2 hari. Kadang-kadang terjadi efek samping
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
yang lebih berat berupa demam tinggi atau kejang yang biasanya
disebabkan oleh unsur pertusisnya. Bila hanya diberikan DT (difteria dan
tetanus) tidak akan menimbulkan efek samping demikian (Markum, 2002).
Vaksin DPT dikemas dalam bentuk flakon 5ml, 10 dosis. Kandungan
vaksin terdiri dari 40 Lf toksoid difteri, 15 Lf toksoid tetanus, 24 (OU)
Bordetalla pertusis (mati) diserapkan ke dalam aluminium fosfat, dan
mertiolat. Secara fisik vaksin DPT berupa cairan tidak berwarna, berkabut
dengan sedikit endapan putih, dan rusak jika terkena panas atau sinar
matahari langsung. Vaksin DPT disimpan dalam lemari es bersuhu 2-8°C
dengan masa kadaluarsa 2 tahun (Mansjoer et.al., 2000).
Vaksin DPT pada penelitian ini digunakan sebagai penginduksi
demam pada tikus. Selain vaksin DPT, induksi demam pada tikus juga
dapat dilakukan dengan penyuntikan protein asing seperti pepton. Prinsip
dari penginduksi demam adalah untuk memacu terbentuknya sitokin-
sitokin pirogen yang memicu naiknya prostaglandin sehingga terjadi
peningkatan set point suhu tubuh (Sherwood, 2001).
Vaksin DPT dapat menyebabkan demam dikarenakan bagian
pertusisnya diambil dari semua sel kuman tersebut (whole cell). Bagian
pertusis ini mengandung lipopolisakarida (LPS) dan berperan sebagai
bahan pirogen yang akan menginduksi terbentuknya sitokin pirogen
seperti interleukin-1 (Katzung dan Payan, 1998). Peningkatan interleukin-
1 (IL-1) menginduksi pembentukan PGE2 di hipotalamus dan menaikkan
set point termostat tubuh sehingga menimbulkan demam (Ganong, 2005).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
B. Kerangka Pemikiran
Membran fosfolipid
Keterangan :
: memacu
: menghambat
Pemberian vaksin
DPT pada tikus putih
Pirogen
Air rebusan daun
sirih merah (Piper
crocatum RP)
Flavonoid
Fagosit mononuklear
terangsang
Sitokin pirogen
Asam arakidonat
PGE2
Enzim
siklooksigenase
(COX) 2
Asetaminofen
Gugus
aminobenzen
Set point
suhu tubuh DEMAM
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
C. Hipotesis
Air rebusan daun sirih merah (Piper crocatum RP) memiliki efek
antipiretik pada tikus putih yang telah diinduksi demam menggunakan vaksin
DPT.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan rancangan pre
and post test with control group design.
B. Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Histologi Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
C. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah tikus putih (Rattus norvegicus) dipilih
berdasarkan kriteria sebagai berikut: jenis kelamin jantan, galur Wistar, berat
badan ±200g, berumur 2-3 bulan, sehat, dan mempunyai aktivitas normal.
D. Teknik Sampling
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive random
sampling dengan kriteria yang telah disebutkan dalam subjek penelitian.
Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Federer yaitu: (k-1) (n-1) > 15
(Smith dan Mangkoewidjojo, 1998).
Jumlah kelompok perlakuan pada penelitian ini sebanyak 5 kelompok,
dengan demikian perhitungan rumus Federer untuk menentukan banyaknya
sampel tiap kelompok sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
(k-1) (n-1) ≥ 15
(5-1) (n-1) ≥ 15
4 (n-1) ≥ 15
4n ≥ 19
n ≥ 5
Keterangan:
k : jumlah kelompok
n : banyak sampel dalam tiap kelompok
Dari perhitungan rumus Federer didapatkan jumlah sampel tiap
kelompok sebanyak 5 sampel. Dengan demikian jumlah sampel pada
penelitian ini adalah 25 sampel.
E. Variabel Penelitian
1. Variabel bebas : air rebusan daun sirih merah (Piper crocatum RP)
2. Variabel terikat : efek antipiretik
3. Variabel luar :
a. dapat dikendalikan :
variasi genetik, isi lambung, umur, jenis kelamin, dan suhu ruangan
b. tidak dapat dikendalikan :
zat pirogen endogen, pH lambung, dan stres
F. Skala Pengukuran Variabel
1. Air rebusan daun sirih merah : skala ordinal
2. Efek antipiretik : skala rasio
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
G. Definisi Operasional
1. Air rebusan daun sirih merah (Piper crocatum RP)
Air rebusan daun sirih merah (Piper crocatum RP) adalah sediaan
yang mengandung campuran komponen aktif dari daun sirih merah. Daun
sirih merah diperoleh dari tanaman sirih merah yang dibudidayakan oleh
perajin tanaman obat dengan usia tanaman ±1 tahun dan berasal dari satu
bibit tanaman. Daun yang digunakan adalah daun yang berumur 1 bulan
berupa daun utuh dan dibuang tangkai daunnya. Daun kemudian
diperhitungkan dosisnya, dipotong kecil-kecil, ditambah air dan direbus
dalam panci aluminium sampai mendidih kemudian disaring dan diambil
airnya. Air rebusan daun sirih merah diberikan secara peroral.
2. Efek antipiretik
Efek antipiretik adalah efek yang ditimbulkan oleh obat atau zat
antipiretik berupa penurunan suhu tubuh. Pengukuran suhu tubuh
dilakukan untuk setiap tikus pada tiap kelompok. Pengukuran suhu pada
tikus dilakukan per-rektal tiap 30’ selama 120’ setelah perlakuan.
Pengukuran suhu dilakukan dengan termometer digital dan menggunakan
skala derajat celcius (°C). Penggunaan termometer digital dikarenakan
termometer digital lebih sensitif terhadap perubahan suhu dan lebih
objektif dalam pembacaan hasil pengukuran dibanding termometer air
raksa. Termometer digital yang digunakan untuk masing-masing
kelompok bermerek dan bertipe sama dengan batere baru.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
H. Rancangan Penelitian
Kelompok K(-)
Tikus
5 ekor
Kelompok K(+)
Tikus
5 ekor
Kelompok D1
Tikus
5 ekor
Kelompok D2 Tikus
5 ekor
Kelompok D3 Tikus
5 ekor
Pengukuran awal suhu rektal tikus
+ vaksin DPT
0,4 cc i.m.
+ 2 ml akuabides
(peroral)
Tikus putih
25 ekor
Tikus dipuasakan selama 6 jam
Tunggu sampai 2 jam
Tunggu sampai 30 menit
Pengukuran awal suhu rektal tikus
Pengukuran awal suhu rektal
tikus
Pengukuran awal suhu rektal tikus
Pengukuran awal suhu rektal tikus
+ vaksin DPT
0,4 cc i.m.
+ vaksin DPT
0,4 cc i.m.
+ vaksin DPT
0,4 cc i.m.
+ vaksin DPT
0,4 cc i.m.
Pengukuran suhu rektal
tikus
Pengukuran suhu rektal
tikus
Pengukuran suhu rektal
tikus
Pengukuran suhu rektal
tikus
Pengukuran suhu rektal
tikus
+ air rebusan daun sirih
merah 6g/200gBB
(peroral)
+ air rebusan daun sirih
merah 4g/200gBB
(peroral)
+ air rebusan daun sirih
merah 2g/200gBB
(peroral)
+ asetaminofen 9mg/200gBB
(peroral)
Pengukuran suhu rektal tikus dan
diulang 30’ selanjutnya
sampai menit
ke 120
Pengukuran suhu rektal tikus dan
diulang 30’ selanjutnya
sampai menit
ke 120
Pengukuran suhu rektal tikus dan
diulang 30’ selanjutnya
sampai menit
ke 120
Pengukuran suhu rektal tikus dan
diulang 30’ selanjutnya
sampai menit
ke 120
Pengukuran suhu rektal tikus dan
diulang 30’ selanjutnya
sampai menit
ke 120
Analisis data
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
Keterangan :
kelompok K(-) : kelompok kontrol negatif (akuabides)
kelompok K(+) : kelompok kontrol positif (asetaminofen 9mg/200gBB)
kelompok D1 : kelompok perlakuan dosis 1 (air rebusan daun sirih merah
2g/200gBB)
kelompok D2 : kelompok perlakuan dosis 2 (air rebusan daun sirih merah
4g/200gBB)
kelompok D3 : kelompok perlakuan dosis 3 (air rebusan daun sirih merah
6g/200gBB)
I. Alat dan Bahan Penelitian
1. Alat penelitian
a. kandang
b. termometer digital
c. timbangan
d. arloji/stopwatch
e. sonde oral
f. jarum suntik dan spuit
g. bekkerglass
h. pengaduk kaca
i. pemanas air
j. mortir
k. termos es
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
2. Bahan penelitian
a. akuabides
b. air
c. daun sirih merah (Piper crocatum RP)
d. alkohol 70%
e. kapas/tissue
e. vaksin DPT
f. asetaminofen tablet
g. pakan tikus
h. es batu
J. Cara Kerja
1. Penentuan dosis air rebusan daun sirih merah
Uji toksisitas yang dilakukan Safithri dan Fahma (2005)
membuktikan bahwa air rebusan daun sirih merah sampai pada dosis
20g/kgBB tikus tidak menyebabkan toksik. Berdasarkan hasil penelitian
tersebut, dapat dikatakan bahwa dosis optimal air rebusan daun sirih merah
yang tidak menyebabkan toksik pada tikus adalah dosis 20g/kgBB tikus
atau 4g/200gBB tikus. Dengan demikian dosis yang diberikan pada
masing-masing kelompok perlakuan adalah:
a. Kelompok perlakuan 1 mendapat dosis setengah dosis optimal yaitu
2g/200gBB.
b. Kelompok perlakuan 2 mendapat dosis optimal yaitu 4g/200gBB.
c. Kelompok perlakuan 3 mendapat 1,5x dosis optimal yaitu 6g/200gBB.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
2. Penentuan dosis asetaminofen
Dosis lazim asetaminofen pada manusia adalah 500mg. Konversi
dosis dari manusia dengan berat badan 70kg ke tikus 200g adalah 0,018
(Ngatidjan, 1991). Maka dosis untuk tikus adalah = 0,018 x 500 =
9mg/200gBB tikus. Asetaminofen 500mg digerus dan disuspensikan ke
dalam larutan CMC 1%, sehingga suspensi asetaminofen yang diberikan
ke tikus sebanyak = 9/500 x 100ml = 1,8ml suspensi asetaminofen.
3. Membuat air rebusan daun sirih merah
Air rebusan daun sirih merah (Piper crocatum RP) dibuat dengan
menambahkan air pada daun sirih merah sebanyak 100g yang telah dipilah
dan dipotong kecil-kecil, ditambahkan air sebanyak 500ml dan direbus
sampai mendidih dalam panci aluminium hingga tersisa volume 100ml
kemudian disaring dan diambil airnya. Perbandingan air dengan daun sirih
merah adalah 1 : 1. Dengan demikian air rebusan daun sirih merah yang
diberikan pada tikus adalah:
a. Kelompok perlakuan dosis 2g/200gBB mendapat:
(100ml x 2g) / 100g = 2ml air rebusan daun sirih merah.
b. Kelompok perlakuan dosis 4g/200gBB mendapat:
(100ml x 4g) / 100g = 4ml air rebusan daun sirih merah.
c. Kelompok perlakuan dosis 6g/200gBB mendapat:
(100ml x 6g) / 100g = 6ml air rebusan daun sirih merah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
4. Langkah penelitian
a. Sebelum perlakuan
Setelah diadaptasikan selama 6 hari di tempat percobaan, tikus
putih dipuasakan 6 jam sebelum perlakuan. Tikus putih kemudian
dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok terdiri atas 5
ekor tikus putih. Temperatur rektal tikus putih diukur terlebih dahulu
untuk mengetahui temperatur normal kemudian tikus putih disuntik
vaksin DPT 0,4cc intramuskuler. Untuk mengetahui berapa derajat
peningkatan suhu tubuh setelah penyuntikan vaksin, maka 2 jam
setelah penyuntikan diberikan, suhu rektal tikus putih diukur terlebih
dahulu.
b. Pemberian perlakuan
Dua jam setelah pemberian vaksin, masing-masing kelompok
mendapat perlakuan sebagai berikut:
1) Kelompok K(-) mendapat 2ml larutan akuabides peroral.
2) Kelompok K(+) mendapat asetaminofen 9mg/200gBB peroral.
3) Kelompok D1 mendapat air rebusan daun sirih merah 2g/200gBB
peroral.
4) Kelompok D2 mendapat air rebusan daun sirih merah 4g/200gBB
peroral.
5) Kelompok D3 mendapat air rebusan daun sirih merah 6g/200gBB
peroral.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
c. Setelah perlakuan
Tigapuluh menit setelah perlakuan, suhu rektal diukur lagi,
sampai percobaan pada menit ke 120 dengan interval 30 menit.
K. Analisis Data
Data ditabulasi dan ditampilkan dalam bentuk grafik. Sebelum dianalisis
lebih lanjut, normalitas data dicek terlebih dahulu. Bila syarat uji parametrik
terpenuhi (distribusi normal dan varians homogen), maka digunakan uji t
berpasangan untuk menguji perbedaan suhu rektal sebelum dan sesudah 2 jam
pemberian vaksin DPT pada setiap kelompok. Apabila syarat uji parametrik
tidak terpenuhi maka uji t berpasangan diganti dengan uji Wilcoxon signed
rank. Uji anova repeated measures digunakan untuk menguji efek antipiretik
pada subjek antarwaktu pengukuran dan subjek antarkelompok. Analisis data
dilakukan pada tingkat signifikansi 0,05.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Data Hasil Penelitian
Setelah dilakukan penelitian mengenai efek antipiretik air rebusan daun
sirih merah (Piper crocatum RP) pada tikus putih, didapatkan data hasil
pengukuran suhu rektal pada masing-masing kelompok seperti yang tertera
pada Tabel 1.
Tabel 1. Rerata Hasil Pengukuran Suhu Rektal Tikus
Kelompok
Suhu rektal tikus ±
simpangan baku (°C)
Suhu rektal tikus setelah perlakuan ± simpangan baku
(°C)
awal 2 jam
setelah
induksi
30 menit 60 menit 90 menit 120 menit
Kontrol (-) 36,64 ± 0,71 38,22 ± 0,59 38,50 ± 0,21 39,08 ± 0,29 38,64 ± 0,26 38,02 ± 0,41
Kontrol (+) 36,02 ± 0,37 37,78 ± 0,40 37,56 ± 0,15 37,60 ± 0,47 37,92 ± 0,54 37,70 ± 0,47
Dosis I 37,00 ± 0,37 38,28 ± 0,42 38,62 ± 0,80 38,42 ± 0,77 38,80 ± 0,59 38,72 ± 0,62
Dosis II 36,16 ± 0,63 37,90 ± 0,39 37,62 ± 0,27 37,96 ± 0,38 37,98 ± 0,63 37,96 ± 0,38
Dosis III 36,96 ± 0,86 38,64 ± 0,31 38,18 ± 0,49 38,14 ± 0,33 38,12 ± 0,36 37,94 ± 0,30
Sumber : data primer, 2010
Keterangan :
Kontrol (-) : kelompok kontrol negatif, 2ml akuabides
Kontrol (+) : kelompok kontrol positif, asetaminofen 9mg/200gBB
Dosis I : kelompok dosis I, 2g/200gBB air rebusan daun sirih merah
Dosis II : kelompok dosis II, 4g/200gBB air rebusan daun sirih merah
Dosis III : kelompok dosis III, 6g/200gBB air rebusan daun sirih merah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
Dari Tabel 1 kemudian dibuat grafik rerata hasil pengukuran suhu rektal
tikus pada setiap kelompok.
Gambar 6. Grafik Rerata Hasil Pengukuran Suhu pada Setiap Kelompok
Keterangan :
Kontrol (-) : kelompok kontrol negatif, 2ml akuabides
Kontrol (+) : kelompok kontrol positif, asetaminofen 9mg/200gBB
Dosis I : kelompok dosis I, 2g/200gBB air rebusan daun sirih merah
Dosis II : kelompok dosis II, 4g/200gBB air rebusan daun sirih merah
Dosis III : kelompok dosis III, 6g/200gBB air rebusan daun sirih merah
Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa suhu rektal pada semua
kelompok meningkat drastis pada 2 jam setelah induksi demam. Hasil
pengukuran suhu rektal setelah perlakuan kemudian menunjukkan hasil yang
relatif konstan pada hampir semua kelompok. Pada kelompok kontrol negatif,
terlihat bahwa setelah mengalami kenaikan suhu rektal pada menit ke-60, suhu
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
awal 2 jam setelah induksi
30 mnt 60 mnt 90 mnt 120 mnt
Suh
u (°
C)
Waktu pengukuran
Kontrol (-)
Kontrol (+)
Dosis I
Dosis II
Dosis III
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
rektal kemudian turun pada menit selanjutnya. Dengan hasil ini, maka
kelompok kontrol negatif belum bisa dijadikan sebagai pembanding karena
hasil pengukuran suhunya kurang ideal. Analisis data selanjutnya
menggunakan kelompok kontrol positif sebagai pembanding untuk menguji
efek antipiretik dari perlakuan yang diberikan.
Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data hasil penelitian,
terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap suhu awal. Analisis terhadap suhu
awal dilakukan dengan menggunakan uji non-parametrik yaitu uji Kruskal-
Wallis karena syarat uji parametrik tidak terpenuhi. Hasil uji Kruskal-Wallis
menunjukkan nilai p>0.05 sehingga suhu awal pada semua kelompok secara
statistik bermakna sama.
B. Analisis Hasil
Analisis statistik terhadap data hasil penelitian dilakukan dengan uji t
berpasangan untuk menguji efek demam dari induksi vaksin DPT pada setiap
kelompok. Jika syarat uji parametrik tidak terpenuhi, uji t berpasangan diganti
dengan uji Wilcoxon signed rank. Uji anova repeated measures digunakan
untuk menguji efek antipiretik pada subjek antarwaktu pengukuran (within
subjects factors) dan pada subjek antarkelompok (between subjects factors).
Analisis statistik dilakukan menggunakan program SPSS for Windows
Release 16.0. Hasil analisis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.
Ringkasan hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
Tabel 2. Hasil Uji T Berpasangan dan Uji Wilcoxon Signed Rank Suhu Awal
dan Suhu Setelah Induksi
No. Kelompok P value Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
Kontrol (-)
Kontrol (+)
Dosis I
Dosis II
Dosis III
0.000
0.004
0.042
0.001
0.014
Signifikan
Signifikan
Signifikan
Signifikan
Signifikan
Sumber: data primer, 2010
Keterangan :
Kontrol (-) : kelompok kontrol negatif, 2ml akuabides
Kontrol (+) : kelompok kontrol positif, asetaminofen 9mg/200gBB
Dosis I : kelompok dosis I, 2g/200gBB air rebusan daun sirih merah
Dosis II : kelompok dosis II, 4g/200gBB air rebusan daun sirih merah
Dosis III : kelompok dosis III, 6g/200gBB air rebusan daun sirih merah
Berdasarkan tabel di atas, terdapat perbedaan yang bermakna (p<0.05)
antara suhu 2 jam setelah induksi dengan suhu awal pada setiap kelompok.
Hal ini menunjukkan bahwa induksi demam dengan vaksin DPT secara
statistik berhasil pada masing-masing kelompok.
Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Anova Repeated Measures Perbandingan Efek
Antipiretik pada Subjek Antarwaktu Pengukuran dan Subjek
Antarkelompok
No. Subjek P value Keterangan
1.
2.
antarwaktu (within subjects)
antarkelompok (between subjects)
0.352
0.008
Tidak Signifikan
Signifikan
Sumber: data primer, 2010
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
Berdasarkan tabel di atas, hasil uji within-subjects effects pada uji anova
repeated measures menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang bermakna
(p>0.05) pada subjek antarwaktu pengukuran. Sementara itu, hasil uji
between-subject effects pada uji anova repated measures menunjukkan adanya
perbedaan yang bermakna (p<0.05) pada subjek antarkelompok. Untuk
mengetahui kelompok perlakuan mana yang berbeda jika dibandingkan
dengan kelompok kontrol positif, maka dilakukan post hoc test dengan
pembanding kelompok kontrol positif.
Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji Post Hoc Perbandingan Efek Antipiretik
No. Kelompok P value Keterangan
1.
2.
3.
kontrol (+) dengan dosis I
kontrol (+) dengan dosis II
kontrol (+) dengan dosis III
0.004
0.788
0.108
Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak signifikan
Sumber: data primer, 2010
Keterangan :
Kontrol (+) : kelompok kontrol positif, asetaminofen 9mg/200gBB
Dosis I : kelompok dosis I, 2g/200gBB air rebusan daun sirih merah
Dosis II : kelompok dosis II, 4g/200gBB air rebusan daun sirih merah
Dosis III : kelompok dosis III, 6g/200gBB air rebusan daun sirih merah
Dari tabel di atas, hasil uji post hoc menunjukkan perbedaan yang
bermakna (p>0.05) antara kelompok kontrol positif dengan kelompok dosis I.
Sedangkan hasil analaisis antara kelompok kontrol positif dengan kelompok
dosis II dan dosis III menunjukkan tidak adanya perbedaan yang bermakna
(p<0.05).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
Adanya perbedaan yang bermakna berarti kelompok dosis I tidak
menimbulkan efek antipiretik dibanding kelompok kontrol positif. Sedangkan
tidak adanya perbedaan yang bermakna berarti kelompok dosis II dan dosis III
menimbulkan efek antipiretik yang sebanding dengan kelompok kontrol
positif.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
BAB V
PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pengukuran suhu rektal tikus putih, suhu awal pada
semua kelompok terlihat relatif sama. Setelah dilakukan induksi demam, suhu
rektal meningkat drastis pada setiap kelompok. Suhu rektal setelah perlakuan
menunjukkan hasil yang relatif konstan pada hampir semua kelompok. Akan
tetapi pada kelompok kontrol negatif, suhu rektal yang diharapkan terus
mengalami kenaikan justru mengalami penurunan pada menit ke-90 sampai menit
ke-120. Dengan hasil ini, kelompok kontrol negatif tidak bisa dijadikan sebagai
pembanding efek antipiretik karena hasil pengukuran suhunya kurang ideal.
Analisis selanjutnya menggunakan kelompok kontrol positif sebagai pembanding
efek antipiretik.
Kurang idealnya hasil pengukuran suhu pada kelompok kontrol negatif
kemungkinan disebabkan oleh faktor endogen maupun eksogen. Faktor endogen
yang kemungkinan berpengaruh adalah faktor hipotalamus dan substansi endogen
yang berefek antipiretik. Sherwood (2001) menjelaskan bahwa kelainan pada
hipotalamus dapat mengurangi respon pusat termoregulasi di hipotalamus
terhadap demam. Dalal dan Zhukovsky (2006) juga menyebutkan bahwa sitokin
lain seperti IL-10 dan substansi endogen seperti arginin vasopressin, melanocyte-
stimulating hormone (MSH), dan glukokortikoid dapat melawan respon demam
sehingga durasi demam dapat berlangsung lebih singkat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
Hasil pengukuran suhu awal diuji terlebih dahulu untuk mengetahui
homogenitas antar subjek penelitian. Hasil uji Kruskal-Wallis memberikan nilai
p>0.05 sehingga suhu awal antar kelompok secara statistik sama. Tidak adanya
perbedaan pada suhu awal menunjukkan bahwa semua subjek dalam penelitian ini
adalah homogen.
Hasil pengukuran suhu rektal menunjukkan bahwa suhu setelah induksi
mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan suhu awal. Uji t
berpasangan dan uji Wilcoxon signed rank memberikan nilai p<0.05 pada semua
kelompok. Hal ini berarti induksi demam yang dilakukan dengan menggunakan
vaksin DPT berhasil pada semua kelompok. Hal tersebut mendukung teori bahwa
pemberian vaksin DPT dapat menimbulkan demam. Katzung dan Payan (1998)
menjelaskan bahwa dalam vaksin DPT terdapat bahan pirogen berupa
lipopolisakarida (LPS) dari kuman Bordetella pertusis. Dijelaskan oleh Sherwood
(2001) dan Guyton (2007) bahwa LPS ini akan memicu terbentuknya sitokin-
sitokin pirogen seperti IL-1, IL-6, dan TNF-α. Menurut Gelfand (2005), sitokin
pirogen tersebut akan meningkatkan ekspresi enzim COX-2 sehingga memicu
peningkatan produksi prostaglandin. Peningkatan prostaglandin akan menaikkan
set point termoregulasi tubuh sehingga terjadi demam.
Untuk menguji efek antipiretik, maka dilakukan uji statistik pada subjek
antarwaktu pengukuran dan subjek antarkelompok. Uji yang dipakai adalah uji
anova repeated measures. Hasil uji efek antipiretik pada subjek antarwaktu
pengukuran memberikan nilai p>0.05. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada
perbandingan antarwaktu pengukuran, efek antipiretik yang diharapkan belum
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
terlihat. Hal ini kemungkinan karena waktu pengamatan kurang lama dan jeda
waktu pengukuran yang singkat. Wilmana dan Gan (2007) menyebutkan bahwa
asetaminofen memerlukan waktu 1-3 jam untuk mencapai masa paruh plasma.
Flavonoid dalam air rebusan daun sirih merah juga masih tercampur dengan
senyawa lain. Hal ini kemungkinan berpengaruh terhadap proses absorbsi dan
konjugasi flavonoid di dalam tubuh.
Uji efek antipiretik pada subjek antarkelompok memberikan nilai p<0.05.
Hal tersebut menunjukkan bahwa di antara kelompok kontrol positif, kelompok
dosis I, dosis II, dan dosis III minimal ada dua kelompok yang berbeda. Hasil uji
post hoc menunjukkan bahwa kelompok yang berbeda dengan kelompok kontrol
positif adalah kelompok dosis I, sedangkan kelompok dosis II dan dosis III tidak
berbeda jika dibandingkan dengan kelompok kontrol positif. Dengan hasil
tersebut, kelompok dosis I disimpulkan tidak memiliki efek antipiretik dibanding
kelompok kontrol positif, sedangkan kelompok dosis II dan dosis III memiliki
efek antipiretik yang sebanding dengan kelompok kontrol positif.
Tidak adanya efek antipiretik pada kelompok dosis I (pemberian air rebusan
daun sirih merah dosis 2g/200gBB) kemungkinan karena kandungan flavonoid
dalam sediaan tersebut belum cukup untuk menghasilkan efek antipiretik.
Munculnya efek antipiretik pada kelompok dosis II (pemberian air rebusan daun
sirih merah dosis 4g/200gBB) dan dosis III (pemberian air rebusan daun sirih
merah dosis 6g/200gBB) kemungkinan karena kandungan flavonoid dalam
sediaan tersebut sudah mencukupi untuk menghasilkan efek antipiretik.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
Hasil penelitian ini mendukung pernyataan Singh et al. (2000), Mutalik et
al. (2003), dan Venkatesh et al. (2003) yang menyatakan bahwa flavonoid
memiliki aktivitas antipiretik selain aktivitasnya sebagai analgesik dan
antiinflamasi. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang
membuktikan bahwa tanaman yang mengandung flavonoid memiliki efek
antipiretik seperti tanaman sambiloto (Setoaji, 2004), brotowali (Ernitawati,
2004), daun sirih hijau (Hastuti, 2007), semak bunga putih (Owoyele et.al., 2008),
dan bayam duri (Kumar et.al., 2009).
Kelemahan dari penelitian ini terletak pada hasil pengukuran kelompok
kontrol negatif yang kurang ideal sehingga kelompok ini tidak bisa dijadikan
pembanding. Pemakaian sediaan air rebusan kemungkinan berpengaruh terhadap
kecilnya efek antipiretik yang dihasilkan. Hal ini mungkin berbeda jika sediaan
sirih merah yang dipakai dalam bentuk ekstrak. Kandungan flavonoid dalam air
rebusan daun sirih merah juga masih tercampur dengan senyawa lain. Hal ini
dapat menyebabkan kerancuan apakah efek antipiretik daun sirih merah
dikarenakan kandungan flavonoidnya atau justru senyawa lain dalam daun sirih
merah tersebut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
BAB VI
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
1. Air rebusan daun sirih merah (Piper crocatum RP) dosis 2g/200gBB tidak
memberikan efek antipiretik pada tikus putih yang telah diinduksi demam
menggunakan vaksin DPT.
2. Air rebusan daun sirih merah (Piper crocatum RP) dosis 4g/200gBB dan
dosis 6g/200gBB memberikan efek antipiretik pada tikus putih yang telah
diinduksi demam menggunakan vaksin DPT.
B. Saran
1. Penelitian lebih lanjut terhadap efek antipiretik air rebusan daun sirih
merah (Piper crocatum RP) dengan metode dan sediaan yang lain seperti
bentuk ekstrak.
2. Penelitian lebih lanjut komponen-komponen kimia daun sirih merah
(Piper crocatum RP) yang berperan terhadap efek antipiretik.