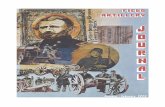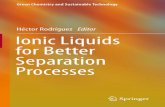Dr. Miswari, M.Ud Editor: Teuku Zulman Sangga Buana
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Dr. Miswari, M.Ud Editor: Teuku Zulman Sangga Buana
1
PERBANDINGAN WUJUDIAH HAMZAH FANSÛRÎ
DAN FILSAFAT MULLA SADRÂ
Penulis: Dr. Miswari, M.Ud
Editor: Teuku Zulman Sangga Buana
2
PRAKATA
Bismillâhirrahmânirrahîm
Alhamdulillah. Radhitu bî‘llahi Rabba wâ bî Islamî dînâ wa bî Muhammadin
Nabiya wa Rasûla. Puji syukur ke hadrat Allah yang telah melimpahkan wujûd
kepada segenap makhluk. Dengan Rahman dan Rahim-Nya kita dapat memiliki
kesadaran melalui jiwa sehingga dapat merasakan segala Jamal dan Jalal-Nya.
Salawat dan salam kepada Insan Kamil, manusia sempurna, Nabi Muhammad
sallalahu ‘alaihi wasalllam. Berkat cahaya beliau manusia alam semesta ini tegak
teratur. Kepada beliaulah kita mengharapkan syafaat di hari akhirat.
Inspirasi dasar menulis buku yang berangkat dari disertasi ini, dengan tema
tentang kajian perbandingan Wujudiah Hamzah Fansûrî dan filsafat Mullâ Sadrâ,
berangkat dari kesadaran pentingnya menggali masa lalu untuk mencari masa depan
dalam rangka menyongsong Indonesia maju dengan eksistensi Islam sebagai agama
yang kosmopolit yang teguh dengan nilai-nilai inklusif. Langkahnya antara lain
dengan menggali khazanah tasawuf dan filsafat yang penuh dengan nilai toleransi
sebagaimana ajaran Hamzah Fansûrî.
Di samping itu, penelitian ini juga dimotivasi oleh kesadaran pentingnya
menggali di antara hal yang masih menjadi misterius dalam ajaran Hamzah Fansûrî
yakni, berdasarkan penelusuran saya, ajarannya benar-benar identik dengan Ibn
‘Arabî. Tetapi yang mengherankan adalah kenapa Nûr al-Dîn al-Ranîrî selalu
konsisten menganggap ajaran Hamzah Fansûrî itu sesat. Sehingga ajaran Hamzah
Fansûrî benar-benar sangat penting untuk terus-menerus diteliti melalui berbagai
pendekatan dan pada berbagai aspeknya. Ajaran Hamzah Fansûrî sebenarnya sangat
dibutuhkan dewasa ini untuk menawarkan alternatif atas berbagai persoalan ilmiah
dan persoalan akademik. Signifikansi ajaran Hamzah Fansûrî dirasakan oleh banyak
peneliti. Beberapa artikel jurnal mutakhir hadir untuk menunjukkan efektivitas ajaran
Hamzah Fansûrî sebagai alternatif berbagai masalah aktual. Sayangnya, artikel-
artikel yang sebenarnya berfokus pada dimensi aksiologis ajaran Hamzah Fansûrî itu
harus diberikan porsi yang besar untuk menjelaskan bahwa Hamzah Fansûrî itu tidak
sesat dan ajarannya adalah tauhid yang lurus. Saya berharap, penelitian ini dapat
membantu penelitian-penelitian aksiologis serupa sehingga tidak lagi perlu
mengawali artikel-artikelnya dengan uraian panjang lebar untuk menjelaskan bahwa
ajaran Hamzah Fansûrî itu tidak sesat dan sangat kontributif.
Sementara pada aspek sosial, berkembangnya radikalisme yang terjadi cukup
parah, ketika ditelusuri akarnya, antara lain ditemukan bahwa itu terjadi akibat krisis
identitas, krisis intelektualitas, dan krisis spiritualitas yang dialami generasi muda,
khususnya para mahasiswa. Mereka merasa tidak menemukan solusi atas krisis itu di
kampusnya. Sehingga mencarinya di lembaga-lembaga tertentu. Sayangnya, banyak
lembaga yang menjadi destinasi mereka mengajarkan jalan pintas sehingga hasilnya
muncul sikap eksklusif dalam membentuk identitas, kegalatan sistem berfikir dalam
membentuk intelektualitas, dan sikap radikal dalam aktualiasasi spiritualitas. Tiga
krisis tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan reformasi pembelajaran keagamaan.
Penelitian ini tidak lepas dari semangat Nurcholish Madjid yang mengingatkan
bahwa banyak sekali problem-problem mutakhir dapat ditemukan solusinya melalui
kajian atas khasanah intelektual masa lalu. Istilahnya, ,enggali masa lalu untuk
3
menemukan masa depan. Penulis yakin semangat keilmuan Hamzah Fansûrî dan
Mullâ Sadrâ memiliki sangat banyak kandungan nilai positif yang dapat ditawarkan
untuk mengatasi berbagai problem kebangsaan kita, khususnya problem sosial,
keagamaan, dan keilmuan. Cak Nur juga pernah mengingatkan, supaya bangsa kita
dapat maju dalam ilmu pengetahuan, kita jangan ragu untuk mengakses literatur
Persia. Saya yakin anak bangsa kita yang punya bekal tradisi keagamaan yang kuat
tidak akan latah dalam mengakses dan mempelajari literatur asing yang memiliki
tradisi yang berbeda.
Sekalipun merupakan karya pribadi, penulisan buku yang berangkat dari
disertasi program doktor konsentrasi Filsafat Islam Sekolah Pascasarjana Universitas
Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini melibatkan berbagai pihak yang
telah memberikan bantuan, kemudahan, serta bimbingan sejak awal perkuliahan
sampai diselesaikannya naskah ini. Untuk itu, dengan segala ketulusan hati, penulis
menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada
yang terhormat Rektor UIN Jakarta, Direktur SPs Prof. Phil. Asep Saepudin Jahar,
Ph.D, Ketua Program Studi Doktor, Prof. Dr. Didin Saifuddin, MA. Terima kasih
teak terhingga kepada Prof. Dr. Abdul Aziz Dahlan dan Prof. Dr. Abdul Hadi W.M.,
sebagai dosen pembimbing. Berikutnya terima kasih kepada Prof. Dr. Amsal
Bakhtiar, Prof. Dr. Achmad Syahid, M.Ag. dan Prof. Dr. IIk Arifin Mansurnoor, MA.
yang telah menjadi penguji dalam ujian promosi. Terima kasih kepada seluruh
karyawan SPs UIN Jakarta atas pelayanannya yang sangat luar biasa.
Terima kasih Program Beasiswa MORA 5000 Doktor sekaligus Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang
telah memberikan biaya studi. Terima kasih Rektor IAIN Langsa yang telah
memberikan tugas belajar. Terima kasih staf Perpustakaan Pascasarjana UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta dan Perpustakaan STAI Sadra yang telah memberikan ruang
kondusif dalam melakukan penelitian. Terima kasih keluarga tercinta yang telah
memberi banyak dukungan dan bersedia banyak waktu untuk mereka banyak saya
ambil dalam melakukan pembelajaran, riset, dan penulisan.
Tidak ketinggalan ucapan terima kasih kepada: Sahabat sekaligus saudara
saya Mulyani, M.Ud. yang telah berkenan menghadiahkan berjilid-jilid koleksi
perpustakaan pribadinya baik itu karya Mullâ Sadrâ, Ibn Sînâ, Ibn ‘Arabȋ, dan
Hamzah Fansûrî untuk riset dan perkenannya berdiskusi tentang filsafat dan tasawuf
falsafi; Sahabat sekaligus guru saya Muhammad Nur Jabir dan Dr. Cipta Bakti Gama
yang telah berkenan menjelaskan kaidah-kaidah sulit dalam filsafat dan tasawuf
falsafi; Sahabat sekaligus rekan seperjuangan saya Muhammad Alkaf, Mirza Ardi,
Muhajir Al-Fairusy, Teuku Jafar Sulaiman, dan Khairil Miswar yang senantiasa
bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi tentang berbagai tema; Sahabat
sekaligus senior, Reza Idria, Ph.D dan Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Ph.D,
yang selalu memberikan semangat dan dukungan; Rekan-rekan mahasiswa S3 di SPs
UIN Jakarta, khususnya Dr. Mukhtar, MA;. Rekan-rekan seperjuangan serta berbagai
pihak yang tidak dapat disebut satu persatu di ruang yang terbatas ini.
Secara khusus, ucapan terima kasih disampaikan kepada almarhum ayah
saya, Usman Banta Leman yang telah bersusah payah menyekolahkan saya. Semoga
segala kebaikan yang saya hasilkan dapat menjadi amal jariah untuk beliau. Demikian
juga ibu saya, Saidah Banta Raden. Ucapan beliau waktu saya masih kelas empat
4
MIN, “Walau bagaimanapun harus sekolah”, senantiasa terngiang di kepala sehingga
selalu menjadi energi bagi saya untuk melalui segala macam rintangan dalam
menuntut ilmu. Tidak lupa terima kasih kepada guru mulai dari MIN hingga UIN,
khususnya Ibu Si yang telah mengajarkan saya membaca, dan Ibu Ana yang telah
mengajarkan saya berhitung. Semoga segala kebaikan ilmu dapat menjadi amal jariah
mereka semua.
Kemudian terima kasih kepada editor yang membantu merapikan tulisan ini.
Terima kasih kepada penerbit yang telah membantu menerbitkan karya ini sehingga
dapat berhadir di hadapan pembaca.
Saya berharap semua orang yang telah berbuat baik selalu diberikan
kemudahan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Saya berharap semua rakyat Indonesia
menjadi manusia yang makmur, sejahtera, berbahagia, jauh dari segala mara bahaya,
dan saling mengasihi. Amin.
Hormat saya,
Miswari
Penulis
5
PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN
Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam buku ini berdasarkan ALA-
LC Romanization Tables.
Konsoson
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
bā’ b be ب
tā’ t te ت
thā’ th te dan ha ث
jīm j je ج
ḥā’ ḥ ha [titik di bawah] ح
khā’ kh ka dan ha خ
dāl d de د
dhāl dh de dan ha ذ
rā’ r er ر
zāy z zet ز
sīn s es س
shīn sh es dan ha ش
ṣād ṣ es [titik di bawah] ص
ḍād ḍ de [titik di bawah] ض
ṭā’ ṭ te [titik di bawah] ط
ẓā ẓ zet [titik di bawah] ظ
ayn koma terbalik di atas‘ ع
ghayn gh ge dan ha غ
fā’ f ef ف
qāf q qi ق
kāf k ka ك
lām l el ل
mīm m em م
nūn n en ن
wāw w we و
hā h ha ه
hamzah ˊ apostrof ء
yā’ y ye ي
Vokal
Vokal Tunggal
Tanda Nama Huruf Latin Nama
- fatḥah a a
- kasrah i i
6
- ḍammah u u
Vokal Rangkap
Tanda dan Huruf Nama Huruf Latin Nama
و - fatḥah dan wāw aw a dan we
fathah dan yā’ ay a dan ye ي-
Vocal Panjang
Tanda dan Huruf Nama Huruf Nama
fatḥah dan alif ā a dan garis di atas ا-
mad dan alif آ
kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas ي-
ḍammah dan wāw ū u dan garis di atas و-
Kata Sandang:
Kata sandang (ال) dilambang dengan huruf (al), baik yang diikuti dengan huruf
shamsīyah (huruf yang dapat penyebabkan peleburan huruf lām sebagai artikel
menjadi bunyi yang sama dengan huruf tersebut), maupun yang diikuti huruf
qamarīyah (huruf yang tidak menyebabkan peleburan huruf lam sebagai artikel).
Kata sandang ini ditulis dengan tanda (-) terpisah dari kata yang mengikuti.
Tā’ Marbūṭah:
1. Jika kata diakhiri dengan tā’ marbūṭah (ة), atau kata tersebut diikuti oleh kata
sandang (ال), serta bacaan keduanya dipisah, maka ditransliterasikan dengan
huruf (h).
2. Jika kata berakhiran (ة) dikontruksi (iḍāfah), maka ditransliterasikan dengan (t).
7
DAFTAR ISI
PRAKATA
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
BAB II TEORI WUJÛD DALAM FILSAFAT DAN WUJUDIAH
A. Teori Wujûd dalam Filsafat Islam
B. Teori Wujûd dalam Wujudiah
C. Pemaknaan atas Teori Wujûd dalam Filsafat dan Wujudiah
BAB III KONSEP WUJUDIAH HAMZAH FANSÛRÎ
A. Kehidupan dan Karya Hamzah Fansûrî
B. Prinsip Dasar Ajaran Hamzah Fansûrî
1. Itikad Para Pesuluk
2. Sifat Haqq Ta’ala
3. Konsep Ta’ayyûn
4. Manusia sebagai Anak Dagang
C. Analogi Kontekstual Wujudiah Hamzah Fansûrî
1. Tanah dan Perabotan Rumah Tangga sebagai Wujûd Mendasar
2. Matahari dan Sinarnya sebagai Pemberian Wujûd
3. Catur dan Buah Catur Sebagai Hubungan Ketunggalan dan
Kemajemukan
4. Laut dan Ombak sebagai Makhluk Menjadi Jejak Ilahi
5. Analogi-analogi Sekunder sebagai Berbagai Penjelasan Wujudiah
D. Pemaknaan Wujudiah Hamzah Fansûrî
BAB IV KONSEP FILSAFAT WUJÛD MULLÂ SADRÂ
A. Kehidupan dan Karya Mullâ Sadrâ
B. Prinsip Dasar Pemikiran Mullâ Sadrâ
1. Ontologi Pemikiran Mullâ Sadrâ
2. Epistemologi Pemikiran Mullâ Sadrâ
C. Konsep Penting Ajaran Filsafat Mullâ Sadrâ
1. Kemendasaran Wujûd (Ashalat al-Wujûd)
2. Gradasi Wujûd (Tâskîk al-Wujûd)
3. Kefakiran Akibat dalam Kausalitas (Illiyah)
4. Hakikat Sederhana (Basith al-Haqîqah)
5. Gerak Substansi (al-Harakah al-Jawhayiah)
6. Kesatuan Subjek dan Objek (Ittihad Aqil wa Ma’qûl)
D. Pemaknaan Filsafat Mullâ Sadrâ
8
BAB V ANALISIS PERBANDINGAN WUJUDIAH HAMZAH FANSURI DAN
FILSAFAT MULLÂ SADRÂ
A. Persamaan Wujudiah Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ
1. Univokasi dan Kemendasaran Wujûd
2. Pengenalan Diri Sebagai Langkah Menuju Pengetahuan Sejati
3. Ilmu Hudhûrî sebagai Pengetahuan Sejati
4. Eksistensi Alam Potensial
5. Kefakiran Mutlak Makhluk kepada Khalik
B. Perbedaan Wujudiah Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ
1. Perbedaan Konteks Kebudayaan
2. Perbedaan Pemahaman atas Status Kemajemukan Realitas Eksternal
3. Multi Perspektif Varian dan Sasaran Kritikan
C. Pemaknaan Perbandingan Wujudiah Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ
BAB VI PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA
GLOSARI
DAFTAR INDEKS
BIODATA PENULIS
9
BAB I
PENDAHULUAN
Diskursus tentang wujûd merupakan salah satu pembahasan penting dalam
pemikiran Islam, baik itu filsafat (al-hikmah), tasawuf (‘irfân), maupun teologi
(kalâm). Diskursus ini merupakan inti dari metafisika Islam. Perbedaan prinsip
pemikiran dalam tiap-tiap varian pemikiran Islam (filsafat, tasawuf, dan teologi)
sangat ditentukan oleh pendekatan masing-masing yang berbeda terhadap wujûd.
Secara objektif, kata wujûd berasal dari akar kata (masdar) wu-ji-da yang
berarti ditemukan sehingga biasanya diterjemahkan menjadi being atau existence
dalam bahasa Inggris. Secara subjektif, kata wujûd berasal dari akar kata (masdar)
wa-ja-da yang berarti menemukan sehingga biasanya diterjemahkan menjadi finding
dalam bahasa Inggris1. Bentuk fi’il dari akar kata tersebut banyak dijumpai dalam Al-
Qur’an, seperti QS. 3: 37, 18: 86, 27: 23, 93: 7, 4: 43,18: 69, dan 7: 1572.
Sementara itu, bentuk masdar hanya ditemukan sebagai wijd, yaitu dalam QS.
65: 66. Secara objektif, kata wujûd berposisi pada ranah ontologis yang dimaknai
sebagai yang ada. Dalam konteks ini, wujûd pada realitasnya adalah sesuatu yang ada
secara mutlak. Sementara secara subjektif, wujûd adalah sesuatu yang dicapai
manusia melalui usaha (riyâdhah) untuk menemukan realitas melalui penyingkapan
spiritual (mukasyafah).
Acuan kata wujûd sebenarnya dapat dialamatkan kepada segala sesuatu yang
dapat diakui keberadaannya (mawjûdat). Pengetahuan akan wujûd bersifat a priori
atau terbukti dengan sendirinya (badȋhȋ). Pengetahuan akan wujûd itu bersifat
hudhurȋ. Setiap orang dapat mengetahui keberadaan lebih dahulu sebelum konsep-
konsep dipahami melalui sistem hûshûlȋ yang meniscayakan adanya konsepsi
(tasawur) dan afirmasi (tasydiq).
Setiap entitas (mawjûdat) terdiri atas dua hal, yakni adakah ia dan apakah itu.
Pertanyaan pertama adalah keberadaannya (mawjûd). Pertanyaan kedua adalah
keapaannya (mâ huwâ). Keberadaannya adalah wujûd, sementara keapaannya adalah
mahiyah. Keberadaan sesuatu dipahami secara lebih jelas dibandingkan keapaannya3.
Wujûd itu tidak dapat didefinisikan karena untuk mendefinisikan sesuatu perlu
menggunakan hal lain yang lebih dipahami. Namun, tidak ada yang lebih terang dan
jelas dibandingkan wujûd itu sendiri4.
Karena wujûd dinisbahkan pada setiap sesuatu yang ada, dapat dinisbahkan
pada Haqq Ta’ala dan segala makhluqat. Oleh mutakallimȋn, wujûd bagi Haqq Ta’ala
1 Kholid Al-Walid, Tasawuf Filosofis, Menyelam Samudra Ilmu Tasawuf, (Jakarta:
Sadra Press, 2020), 41. 2 Kautsar Azhari Noer, Ibn ‘Arabi: Wahdat Al-Wujûd Dalam Perdebatan (Jakarta:
Paramadina, 1995), 42. 3 Muḥammad Ḥusein Thabâthabâ’î, Bidâyah Al-Ḥikmah. (Qum: Muʽassasah an-Nasyr
al-Islâmî), 1428H, 1-2. 4 Seyyed Hossein Nasr, Islamic Philosophy From Its Origin to the Present (New York:
State University of New York Press, 2006), 66.
10
memiliki acuan yang berbeda dengan wujûd. Wujûd Haqq Ta’ala lain, wujûd
makhluqat lain. Pemahaman demikian memaknai wujûd itu ekuivokal. Asal katanya
tunggal, tetapi acuannya beragam. Sementara bagi penganut tasawuf wujudiah
(tasawuf falsafi), meyakini kata wujûd itu acuannya tunggal, yakni hanya dialamatkan
kepada Haqq Taa’ala. Sementara segala mawjûdat itu diyakini hanya sebagai
manifestasi atau tajallȋ dari Wujûd yang Tunggal, yakni Haqq Ta’ala. Pemahaman
demikian memaknai wujûd itu univokal. Asal katanya tunggal, acuannya juga
tunggal.
Sementara bagi para filosof, khususnya aliran al-Hikmah al-Masyâ'iyyah,
wujûd itu secara konseptual memang diakui tunggal, namun pada realitas diakui
beragam. Oleh al-Hikmah al-Masya’iyyah, setiap mawjûdat itu diyakini memiliki
wujûd yang berbeda. Perbedaan pandangan atas wujûd memunculkan perdebatan
serius dalam diskursus pemikiran Islam. Sementara aliran filsafat al-Hikmah al-
Isyrâqiyyah memandang wujûd sebagai tambahan bagi mahiyah yang dipandang
sebagai dasar bagi realitas. Adapun aliran filsafat al-Hikmah al-Muta’alliyah
memandang berpandangan kebalikan dengan al-Hikmah al-Masya’iyyah dengan
memandang wujûd sebagai dasar realitas.
Perbedaan pandangan antarvarian pemikiran Islam ini memunculkan
perdebatan serius dan panjang karena yang mereka perbebatkan adalah pemahaman
masing-masing yang berbeda dalam dimensi inti metafisika pemikiran Islam, yakni
mengenai perdebatan wujûd. Keunikan antar ajaran dalam tradisi pemikiran Islam,
khususnya dalam tasawuf falsafi dan filsafat berlandaskan pada prinsip ontologi tiap-
tiap pemikir, yakni pemahaman mereka akan wujûd.
Dalam diskursus pemikiran Islam, antara tasawuf, filsafat, dan teologi selalu
terjadi perdebatan. Tiga varian pemikiran ini memiliki landasan epistemologis yang
berbeda. Tasawuf menjadikan penyingkapan batin (‘irfânî) sebagai landasan utama
pengetahuan5. Kalaupun menerima wahyu dan rasio, itu akan dimaknai sebagaimana
penyingkapan batin. Filsafat menjadikan rasio (burhânî) sebagai basis pengetahuan.
Kalaupun menerima wahyu (bayânî) dan penyingkapan batin, itu akan dimaknai
secara rasional6. Sementara teologi menjadikan wahyu sebagai landasan
pengetahuan7. Sementara bila menerima rasio dan penyingkapan batin, itu hanya akan
diterima sejauh ia sesuai dengan wahyu. Perbedaan epistemologi dari tiap-tiap varian
keilmuan ini tentunya tidak terlepas dari perbedaan pemahaman ontologisnya
masing-masing, khususnya mengenai pemahaman tentang wujûd. Bahkan dalam satu
varian sekalipun, antar pemikirnya memiliki perbedaan pemikiran yang signifikan8.
Dalam tasawuf Wujudiah, wujûd diyakini sebagai satu-satunya realitas
Tunggal yang dinisbahkan kepada Haqq Ta’ala. Pandangan ini menjadi polemik bagi
kalangan mutakallimîn karena ditemukan bahwa selain Allah juga terdapat wujûd
5 Mehdi Haeri Yazdi, The Principles of Epistemology in Islamic Phlosophy:
Knowledge by Presence (New York: State University of New York Press, 1992), 14. 6 Ismail Fahmi Arrauf Nasution, “Mencerna Akar Filsafat Dalam Islam,” Ulumuna 17,
no. 1 (November 8, 2017): 1–18, http://ulumuna.or.id/index.php/ujis/article/view/236. 7 Harun Nusution, Teologi Islam (Jakarta: UIP, 2006), 99. 8 Nani Widiawati, Pluralisme Metodologi: Diskursus Sains, Filsafat, Dan Tasawuf,
(Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), 3–4.
11
lainnya, seperti wujûd alam semesta. Pemahaman Wujudiah mengenai wujûd
memunculkan anggapan bahwa Haqq Ta’ala diserupakan dengan alam. Padahal,
sebagaimana menurut pandangan mutakallimîn, Tuhan itu mukhallafatuhû lil
hawadtsî, tidak ada apa pun yang menyerupainya. Tuhan itu tanzîh. Sementara
pandangan Wujudiah dianggap oleh mutakallimîn menjadikan memaknai Tuhan
dengan sangat tasybîh.
Problem dalam diskursus wujûd perspektif Wujudiah dimunculkan oleh Abû
Yazid al-Bistamî (804–874 M) dengan pemahaman yang melihat manusia itu naik
untuk melebur sehingga yang nyata hanya Haqq Ta’ala. Pandangan tersebut disebut
sebagai ittihâd. Demikian pula Abû Mansûr al-Hallaj (858–922 M) dengan
pemahaman yang menyatakan Haqq Ta’ala turun hingga melebur dengan manusia.
Pandangan tersebut disebut sebagai hulûl. Dua konsep tersebut dianggap sebagai
pandangan penyatuan Tuhan dengan manusia secara personal. Nûr al-Dîn al-Ranîrî
(m. 1658 M) menentang keras ajaran tersebut dengan menyebutnya sebagai
Wujudiyah mulhith, yakni iktikad Wujudiah yang sesat.
Ajaran Wujudiah setelah Abû Yazid al-Bistamî dan Abû Mansûr al-Hallaj
dikembangkan oleh Ibn ‘Arabî (1165–1240) yang diistilahkan dengan wahdat al-
wujûd. Bila ittihâd dan hulûl merupakan acuan pengalaman spiritual secara
individual, wahdat al-wujûd merupakan gambaran manifestasi Haqq Ta’ala pada
keseluruhan alam.
Bagi mutakallim, seperti Nûr al-Dîn al-Ranîrî terdapat juga Wujudiah yang
masih menganut tauhid yang benar, yakni Wujudiah muwwahidah, berupa ajaran
Wujudiah yang tidak bertentangan dengan prinsip tauhid Ahlû Sunnah wa al-
Jama’ah. Dalam penilaian Nûr al-Dîn al-Ranîrî, ajaran Ibn ‘Arabî masih dapat
digolongkan sebagai Wujudiah muwwahidah9. Demikian juga ‘Abd al-Ra’uf al-
Sinkilî (1615–1693)10 dan gurunya Ibrâhîm al-Kurânî (1615–1690 M)11
berpandangan bahwa Wujudiah Ibn ‘Arabî masih dapat digolongkan sebagai
Wujudiah muwwahidah selama penafsiran-penafsirannya tidak bertentangan dengan
akidah Asya’ariah.
Wujudiah Hamzah Fansûrî juga oleh Nûr al-Dîn al-Ranîrî dianggap sebagai
ajaran yang sesat12. Sejauh yang dapat ditelusuri, sebagaimana tergambar dalam
Tibyān fī Ma’rifat al-Adyān (Tibyān), klaim utama kesesatan yag dialamatkan kepada
Hamzah Fansûrî, antara lain karena analogi-analogi yang digunakan Hamzah Fansûrî
untuk menerangkan metafisika Wujudiah dianggap menyimpang dan sesat. Misalnya,
analogi biji untuk menganalogikan kanzan makfi, dianggap kufur. Analogi kesatuan
laut dan ombak dan analogi kesatuan matahari dan sinarnya ditentang Nûr al-Dîn al-
9 Syed Muhammad Naquib Al-Attas, A Commentary on the Hujjat Al-Shiddiq of Nûr
Al-Dîn Al-Ranirî ,(Kuala Lumpu: Kuala Lumpu, 1986), 90-92. 10 Oman Fathurahman, Tanbih Al-Masyi: Menyoal Wahdah al-Wujûd : Kasus
Abdurrauf Singkel Di Aceh Abad 17 (Bandung: Mizan, 1999), 171. 11 Oman Fathurahman, Ithaf Al-Dhaki: Tafsir Wahdatul Wujud Bagi Muslim
Nusantara, (Bandung: Mizan, 2012), 65-66. 12, Nûr al-Dîn Al-Ranîrî, Al-Tibyan fî Ma’rifat al-Adyân, ed. Muhammad Kalam Daud
(Banda Aceh: PeNa, 2011), 175.
12
Ranîrî karena dianggap menyerupakan wujûd Haqq ta’ala dan wujûd makhluqat13.
Padahal, iktikad Wujudiah adalah wujûd itu tunggal, sementara mawjûdat pada
makhluqat hanyalah manifestasi atau tajallȋ dari wujûd yang tunggal itu. Perbedaan
pandangan tersebut merupakan bagian penting dari perdebatan metafisika dalam
khazanah pemikiran Islam.
Pada sisi lain, filsafat wujûd Mullâ Sadrâ14 juga menuai polemiknya sendiri
karena di dunia Persia, kajian filosofis yang digandrungi adalah kajian yang tidak
melepaskan diri dari unsur metafisika Persia kuno15. Sementara itu, filsafat Mullâ
Sadrâ mengkritik ajaran Syihab al-Dîn al-Suhrawardî (1153–1191 M)16 secara
mendasar yang mana pemikiran filsafat cahaya Syaikh al-Isyraq itu telah diterima
sebagai sebuah kajian filsafat yang menjunjung tinggi tradisi filsafat Persia yang
bersambung hingga Zoroastrian.
Sebagaimana terjadi di Kepulauan Indonesia dalam perdebatan antara Hamzah
Fansûrî dan Nûr al-Dîn al-Ranîrî, tradisi filsafat di Persia sebagaimana hasil
penelitian Sir Muhammad Iqbal17 menunjukkan bahwa terjadi kontestasi yang
panjang dan rumit antara pandangan monisme yang meyakini kesatuan wujûd dan
dualisme yang meyakini kemajemukan wujûd. Pandangan kesatuan wujûd sangat
berkaitan dengan filsafat Neoplatonisme yang memiliki porsi besar dalam membahas
tentang manifestasi Wujûd yang Esa. Sementara pandangan kemajemukan wujûd
sangat berkaitan dengan filsafat Aristotelian, baik itu pendayagunaan sistem
logikanyanya oleh ilmu kalam maupun pengaruh besarnya terhadap filsafat
Peripatetik Islam (al-Hikmah al-Masyâ'iyyah). Namun demikian, al-Hikmah al-
Masyâ'iyyah sendiri tidak benar-benar bernuansa Aristotelianisme karena telah
sangat banyak mengadopsi Neoplatonisme, antara lain, untuk memenuhi kekurangan
filsafat Aristotelian dalam membahas tema Ilahiah.
Implikasi-implikasi dari pembangunan al-Hikmah al-Masyâ'iyyah ditentang
keras oleh Abû Hamid al-Ghazalî (1058–1111 M) karena dianggap menyimpang dari
prinsip tauhid yang lurus18. Syihab al-Dîn al-Suhrawardî juga melancarkan kritik
mendasar terhadap bangunan dasar pemikiran al-Hikmah al-Masyâ'iyyah, yakni
menunjukkan kemustahilan definisi yang menjadi prasyarat penyusunan silogisme.
Selanjutnya, Ibn Rusyd (1126–1198 M) berusaha membela ajaran al-Hikmah al-
Masyâ'iyyah sekaligus memurnikan filsafat Aristotelian dari pengaruh
Neoplatonisme dalam filsafat Islam19. Terakhir, Mullâ Sadrâ melakukan evalusi
holistik dan sistematis atas berbagai aliran filsafat sebelumnya, mengomentari ilmu
kalam, dan mengakomodir beberapa pandangan Wujudiah untuk membangun sebuah
13 Al-Ranîrî, Nûr al-Dîn, Al-Tibyan fî Ma’rifat al-Adyân…, 168-172. 14 Mulla Sadra, Al-Hikmah Al-Muta’âliyah fî Al-Asfâr Al-‘Aqliyyah Al-Arba’Ah Vol. I
(Beirut: Dar Iḥyâʽ at-Turâts al-‘Arabiy, 2002), 11–15. 15 Allama Sir Muhammad Iqbal, Metafisika Persia: Suatu Sumbangan Untuk Sejarah
Filsafat Islam, (Bandung: Mizan, 1990), 37. 16 Sihabuddin Suhrawardi, “Hikmah Al-Isyrâq,” in Majmû’ah Muśannafât Syaikh Al-
Isyrâq Vol. II (Teheran: Pezhuhesgâh „Olûm-e Insânî va Moțâla‟ât-e Farhangge, 1979), 11. 17 Allama Sir Muhammad Iqbal, Metafisika Persia…, 37-40. 18 Abû Hamid al-Ghazalî, Tahâfut al-Falâsifah. (Kairo: Dâr al-Ma’ârif, t.t.), 9-11. 19 Ibn Rusyd, Tahâfut al- Tahâfut, (Kairo: Dâr al-Ma’ârif, 1964), 18-19.
13
aliran baru dalam filsafat Islam yang dikenal dengan al-Hikmah al-Muta’alliyah20.
Perdebatan-perdebatan ini menunjukkan ketajaman diskursus dalam filsafat Islam.
Demikian juga pada ranah tasawuf filosofis, misalnya dalam kasus
pertentangan antara Hamzah Fansûrî dan Nûr al-Dîn al-Ranîrî, perdebatannya tidak
hanya mengenai cara pandang masing-masing yang berbeda tentang wujûd. Nûr al-
Dîn al-Ranîrî memandang antara Tuhan dan alam memiliki masing-masing wujûd
yang berbeda. Sementara Wujudiah hanya meyakini satu wujûd yang Tunggal yang
dinisbahkan kepada Haqq Ta’ala. Pertentangan tersebut merupakan partikularitas
dari perdebatan besar antara Wujudiah dan teologi Islam (kâlâm). Perdebatan
mutakallimîn dan Wujudiah telah berlangsung lama dan menyebabkan pertikaian
besar. Di Kepulauan Indonesia, pertentangan tersebut telah terjadi sejak Kesultanan
Samudra Pasai antara Syaikh Abd Jalîl yang menganut prinsip kâlâm dan Maharaja
Bakoy yang diduga pengajar Wujudiah21.
Menjadi sebuah keunikan yang sangat menarik untuk diteliti secara komparatif
adalah kenapa meskipun berasal dari dua varian pemikiran yang berbeda, Hamzah
Fansûrî yang merupakan bagian dari pengajar tasawuf falsafi atau Wujudiah dan
Mullâ Sadrâ yang berasal dari varian filsafat, memiliki keidentikan dalam landasan
ontologi, yakni meyakini wujûd itu adalah univokal dan menjadi dasar realitas.
Wujudiah Hamzah Fansûrî dan filsafat Mullâ Sadrâ merupakan kekayaan
khazanah intelektual klasik yang mengandung sangat banyak nilai kebijaksanaan.
Sebagai ajaran yang pernah berkembang pada periode kejayaan Nusantara, Wujudiah
Hamzah Fansûrî bila digali kembali dapat diharapkan menjadi rujukan pembangunan
masyarakat kosmopolit sebagaimana terjadi sebelumnya. Sementara itu, filsafat
Mullâ Sadrâ yang hadir dalam perkembangan tradisi ilmu pengetahuan diharapkan
dapat menjadi pengayaan wawasan intelektual masyarakat dewasa ini, khususnya
tentang pengembangan ilmu pengetahuan untuk mengambil semangat kritis dan
sintesis berbagai varian khazanah ilmu pengetahuan.
Wujudiah Hamzah Fansûrî hadir untuk menyederhanakan suatu gagasan
metafisika yang dianggap sangat rumit dan dilematis yang pernah berkembang dalam
tradisi intelektual Islam. Hamzah Fansûrî dalam karya-karyanya telah mendialogkan
berbagai gagasan kaum sufi sebelumnya. Gagasan-gagasan itu sebagian dianggap
sangat kontroversial. Namun, Hamzah Fansûrî berusaha agar gagasan-gagasan itu
dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat dengan menggunakan bahasa yang
indah dalam bentuk syair-syair dan prosa. Hamzah Fansûrî menggunakan berbagai
analogi yang dekat dengan keseharian masyarakat Melayu supaya ajaran Wujudiah
dapat diterima dengan mudah.
Demikian juga Mullâ Sadrâ dalam konteks yang lain mendialogkan berbagai
varian dalam pemikiran Islam dan melakukan usaha sintesis atas khazanah keilmuan
sebelumnya. Usaha Mullâ Sadrâ juga sesuai dengan konteks perkembangan tradisi
ilmu pengetahuan pada masanya yang sedang berusaha menyintesis berbagai varian
keilmuan dalam tradisi pemikiran Islam. Baik Wujudiah Hamzah Fansûrî maupun
20 Mulla Sadra, Al-Hikmah Al-Muta’âliyah fî Al-Asfâr Al-‘Aqliyyah Al-Arba’Ah Vol.
I…, 12-13. 21 Ali Hasjmy, Ruba’i Hamzah Fansûrî, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,
1976), 1.
14
filsafat Mullâ Sadrâ, hadir ke dalam konteks masyarakatnya masing-masing dan
berusaha menyesuaikan ajarannya dengan perkembangan budaya ilmu pengetahuan
dan sosial masing-masing yang berbeda. Keduanya hadir untuk mendialogkan
gagasan ketuhanan dalam keagamaan dan ilmu pengetahuan dan memperkaya
khazanah ilmu pengetahuan di dalam negerinya masing-masing.
Wujudiah adalah ajaran yang kompatibel untuk setiap zaman karena basis
ajarannya yang sarat nilai mendasar, seperti ketuhanan dan kemanusiaan sehingga
dapat selalu ditawarkan sebagai bagian penting dalam menemukan kesamaan
manusia dalam krisis identitas dan spiritualitas22. Kesamaan itu tidak dicari dari
konstruksi-konstruksi antar kearifan, tetapi melihat kepada dasar diri manusia. Pada
dasar diri, pada fitrah inilah, manusia memiliki kesamaan. Sementara itu, filsafat
Mullâ Sadrâ mengandung kemungkinan memperkaya tradisi filosofis masyarakat
dalam krisis intelektualitas dewasa ini. Pemurnian kedirian manusia yang bernuansa
Ilahiah dan pengembangan ilmu pengetahuan merupakan tuntutan bagi masyarakat
yang ingin maju dalam segala bidang. Maka dari itu, menggali literatur klasik
merupakan bagian dari usaha memajukan peradaban dan ilmu pengetahuan. Agama,
budaya, dan ilmu pengetahuan harus berkembang secara beriringan dalam sebuah
bangsa besar dan masyarakat yang majemuk. Secara khusus, penelitian pemikiran
Hamzah Fansûrî diharapkan dapat mengatasi masalah spiritualitas. Sementara
penelitian pemikiran Mullâ Sadrâ diharapkan dapat mengatasi krisis intelektualitas.
Secara umum, penelitian atas pemikiran dua dua pemikir ini diharapkan dapat
menjadi acuan mengatasi berbagai problem sosial dan keagamaan.
Misalnya, problem disintegrasi agama dan budaya mengandung potensi
penyelesaiannya dalam Wujudiah. Hal ini pernah dibuktikan Syaikh Siti Jenar yang
melakukan pendekatan sosial dan memperingatkan tentang bahaya kemanusiaan
dengan jalan pendekatan Wujudiah sehingga antara kebudayaan dan keagamaan tidak
mengalami perbenturan. Dalam pendekatan tasawuf falsafi perspektif Wujudiah,
yang terjadi adalah harmonisasi dan asimilasi kearifan agama dan kearifan budaya.
Achmad Chodjim23 dalam menganalisis ajaran Syaikh Siti Jenar menunjukkan bahwa
ajaran tasawuf falsafi adalah ajaran yang lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia
dalam mempelajari Islam. Pendekatan humanistik dan eksoterik yang dikedepankan
tasawuf falsafi24 dapat mudah menyesuaikan diri dengan jati diri masyarakat
Kepulauan Indonesia25.
Sementara itu, krisis intelektualitas yang dialami masyarakat dewasa ini perlu
disikapi dengan serius. Berbagai negara di belahan dunia terus-menerus
mengembangkan ilmu pengetahuan di segala bidang. Perkembangan tersebut harus
22 Haidar Bagir, Semesta Cinta, (Bandung: Mizan, 2015), 23. 23 Ahmad Chodjim, Syeikh Siti Jenar: Makna Kematian, (Jakarta: Baca,), 46. 24 KH. Said Aqid Siroj menyimpulkan bahwa tasawuf falsafi memiliki kandungan nilai
yang mendalam dan dapat dijadikan landasan moral dan kultural. KH. Said Aqil Siroj, Allah
dan Semesta: Perspektif Tasawuf Falsafi, (Jakarta: Yayasan Said Aqid Siroj, 2021), 371. 25 Kepulauan-Indonesia yang dimaksud mencakup wilayah Indonesia sekarang dalam
periode sekarang dan jauh ke belakang. Kesesuaian tasawuf falsafi dengan jati diri
masyarakat Indonesia dapat dilihat, Ahmad Chodjim, Syeikh Siti Jenar: Makna Kematian…,
349.
15
dijadikan peluang untuk memperkaya tradisi ilmu pengetahuan bangsa dan
masyarakat. Dalam hal ini, diperlukan sistem sintesis berbagai perkembangan ilmu
pengetahuan untuk membuat perkembangan ilmu pengetahuan memiliki nilai positif.
Dalam hal ini, semangat kritis dan sintesis Mullâ Sadrâ dalam merespons
perkembangan ilmu pengetahuan multidisiplin perlu dikaji dan dijadikan inspirasi.
Hamzah Fansûrî hidup dan berkarier sekitar abad ke-16 pada masa
perkembangan Kerajaan Aceh Darussalam. Pada masa tersebut, masyarakat
Nusantara menjadi sangat kosmopolit. Silang budaya terjadi begitu cepat. Berbagai
etnis menjadi larut. Perekonomian tumbuh pesat. Menariknya, kosmopolitanisme itu
beriringan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa
Wujudiah Hamzah Fansûrî dapat hidup dan berkembang dalam masyarakat
kosmopolit itu. Bahkan, mungkin menjadi pendorong kosmopolitanisme itu. Maka
dengan demikian, untuk menuju kosmopolitanisme baru, masyarakat Indonesia perlu
menghidupkan kembali nilai ajaran Wujudiah Hamzah Fansûrî dan tasawuf falsafi
lainnya.
Ajaran Wujudiah sesuai untuk diajarkan di Indonesia karena memiliki nilai
yang identik dengan penghayatan masyarakat. Maka dari itu, nilai-nilai dari
Wujudiah dapat ditawarkan dan menjadi efektif mengatasi masalah-masalah yang
dihadapi bangsa Indonesia. Atas kesadaran itu, sebagian akademisi dan peneliti
berusaha menghidupkan kembali khazanah tasawuf yang pernah berkembang di
Kepulauan Indonesia, seperti ajaran Syaikh Siti Jenar (1426–1517 M), Syaikh Yusuf
al-Maqassarî (1626–1699 M), Syaikh Abdul Muhyî (1650–1730 M), dan tentunya
Wujudiah Hamzah Fansûrî26. Hal ini juga dilakukan karena sebagian akademisi dan
peneliti melihat, perspektif teologis yang dianggap mapan ternyata perlu diperkaya
kembali27. Hal ini juga yang menjadi alasan beberapa inteligensia berusaha
melakukan pengayaan terhadap konsep teologis28. Akan tetapi, usaha menghidupkan
kembali Wujudiah dengan harapan dapat memberikan kontribusi mengatasi masalah-
masalah dewasa ini mengalami banyak kendala. Di antaranya adalah karena ajaran
tersebut telah menjadi asing bagi masyarakat29.
Di antara nilai-nilai ajaran Wujudiah yang sangat penting untuk dihidupkan
kembali dalam kehidupan masyarakat kontemporer adalah kesadaran bahwa manusia
dan Haqq Ta’ala itu tiada berhijab. Manusia dapat mendayagunakan seluruh fakultas
jiwanya untuk menghidupkan moralitas yang sesuai dengan sifat-sifat yang indah
sebagaimana dalam Asma’ul Husnâ. Bila manusia telah tidak lagi berhijab dengan
Allah, Dia menjadi tangan dalam berbuat, menjadi kaki dalam melangkah, dan
menjadi lisan dalam berucap. Apabila masyarakat demikian dapat terbangun, dapat
26 Syaifan Nur, “Kritik Terhadap Pemikiran Tasawuf Al-Raniri,” Kanz Philosophia :
A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism 3, no. 2 (2013): 137. 27 Jeffry R. Halverson, Theology and Creed in Sunni Islam: The Muslim Brotherhood,
Ash’Arism and Political Sunnism (New York: Palgrave Macmillan, 2010), 59–60. 28 Carool Kersten, Islam In Indonesia: The Contest for Society, Ideas and Values (New
York: Oxford University Press, 2015), 91–92. 29 Peter G. Riddell, “Breaking the Hamzah Fansuri Barrier: Other Literary Windows
into Sumatran Islam in the Late Sixteenth Century CE,” Indonesia and the Malay World 32,
no. 93 (2004): 125–140.
16
mewujudkan masyarakat yang sempurna. Untuk itu, langkah awalnya adalah
menghidupkan kembali semangat ajaran Wujudiah sebagaimana diajarkan para sufi,
termasuk Hamzah Fansûrî. Dengan demikian, ajaran tersebut tidak lagi mengalami
kecurigaan dan penolakan dalam masyarakat.
Filsafat Mullâ Sadrâ juga mengalami kendala serupa. Ajaran tersebut kurang
diterima karena selain penjelasannya yang rumit, juga dicurigai mengandung muatan
nilai yang asing bagi masyarakat Indonesia. Padahal, masyarakat yang telah memiliki
prinsip yang sangat kuat akan mampu menyerap kandungan analisis filosofis, daya
kritis, dan kemampuan sintesis yang dipraktikkan Mullâ Sadrâ dalam membangun
filsafatnya. Filsafat Mullâ Sadrâ awalnya juga ditentang oleh sebagian pemikir di
negerinya. Filsafat tersebut dicurigai telah merevolusi gagasan illuminasi oleh Syihab
al-Dîn al-Suhrawardî yang telah membuat masyarakat Persia bangga karena ajaran
itu memiliki akar tradisi yang mengakar hingga Zoroastrian30.
Namun demikian, penentangan atas filsafat Mullâ Sadrâ di negerinya tidak
berlangsung lama. Ajaran tersebut masih berkembang secara luas di sana hingga hari
ini. Sebaliknya, Wujudiah Hamzah Fansûrî mengalami kemunduran serius setelah
dikritik secara mendalam oleh Nûr al-Dîn al-Ranîrî. Sarjana dari India itu dalam
Ḥujjat al-Siddîq li Daf'i al-Zindîq (Hujjat) menuduh Hamzah Fansûrî mengajarkan
iktikad yang menyamakan Allah dengan makhluk. Tuduhan ini muncul dari
perbedaan paradigma dalam memaknai konsep tentang wujûd. Perspektif yang
berbeda dalam memaknai analogi-analogi yang digunakan dan penerimaan gagasan
beberapa sufi sebelumnya yang dianggap kontroversial menyebabkan Nûr al-Dîn al-
Ranîrî menuduh ajaran Wujudiah Hamzah Fansûrî itu sesat31.
Perbedaan pemahaman adalah pangkal penolakan atas ajaran Wujudiah
Hamzah Fansûrî. Para peneliti yang berusaha menggali nilai aksiologis tentang
Wujudiah Hamzah Fansûrî perlu bekerja keras untuk memperjelas ajaran tersebut
supaya tidak selalu dianggap kontroversial. Usaha yang mereka lakukan di antaranya
adalah memberikan ruang yang besar untuk mengklarifikasi bahwa Wujudiah
Hamzah Fansûrî itu tidak sesat32. Akibatnya, perlu ruang yang panjang untuk
mengurai ajaran tasawuf falsafi, barulah aksiologinya disampaikan33.
Sudah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengklarifikasi ajaran Hamzah
Fansûrî. Itu dilakukan oleh para peneliti yang sangat mendalami pemikiran sufi
30 Allama Sir Muhammad Iqbal, Metafisika Persia…,131. 31 Ismail Fahmi Arrauf Nasution, “Buku Panduan Pengkafiran: Evaluasi Kritis Tibyān
Fī Ma’rifat Al-Adyān Karya Nūr Al-Dīn Al-Ranīrī,” Jurnal Theologia 29, no. 1 (September
2, 2018): 75, http://journal.walisongo.ac.id/index.php/teologia/article/view/2313. 32 Ismail Fahmi Arrauf Nasution, “Termination OF Wahdatul Wujud In Islamic
Civilization In Aceh: Critical Analysis of Ithaf Ad-Dhaki, The Works of Ibrahim Kurani,”
ADDIN 11, no. 2 (August 1, 2017): 401,
http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/view/3356. 33 Lihat misalnya penelitian yang dilakukan oleh Sayifan Nur, “Kritik Terhadap
Pemikiran Tasawuf Al-Raniri”, 137; Nasution, “Buku Panduan Pengkafiran: Evaluasi Kritis
Tibyān Fī Ma’rifat Al-Adyān Karya Nūr Al-Dīn Al-Ranīrī”, 59; Afif Anshori “Kontestasi
Tasawuf Sunnî dan Tasawuf Falsafî di Nusantara”, 309; Ismail Fahmi Arrauf Nasution,
“Humanisasi Pendidikan Islam Melalui Antropologi Transendental Hamzah Fansûrî,”
Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam (2017), 235.
17
Melayu itu. Mereka juga memiliki bekal ilmu bahasa, filsafat, tasawuf, dan
sebagainya. Namun, tetap saja Wujudiah Hamzah Fansûrî asing bagi masyarakat.
Padahal, Wujudiah adalah ajaran yang pernah berjaya di Kepulauan Indonesia34.
Hal ini berbeda dengan yang dialami filsafat Mullâ Sadrâ. Meski sempat
ditentang, itu hanya terjadi sementara. Selanjutnya ajaran Mullâ Sadrâ masih
diapresiasi di tanah kelahirannya dan bahkan tersebar di berbagai kawasan.
Perdebatan keilmuan dalam filsafat Mullâ Sadrâ tidak mengalami klaim pengafiran
sebagaimana dialami Wujudiah Hamzah Fansûrî. Filsafat Mullâ Sadrâ dewasa ini
diperdebatkan antara penggolongannya sebagai tasawuf falsafi dan filsafat. Pengkaji
yang menggolongkan pemikiran Mullâ Sadrâ sebagai ajaran tasawuf, seperti Hasan
Mu’allimî, Hasan Zâdeh Amûlî (1928 M), dan Sayyid Yadullah Yazdan Panah35.
Sementara yang memaknainya sebagai filsafat, seperti Sayyid Hussîn Thabattâbâ'i
(1904–1981 M) dan Muhammad Taqî Misbah Yazdî (1935–2021 M).
Indonesia sebagai negara yang telah memiliki tradisi keagamaan yang kuat
perlu mengambil semangat dari pemikiran Mullâ Sadrâ tanpa kehilangan
identitasnya. Elemen penting yang dapat diambil dari semangat filsafat Mullâ Sadrâ,
antara lain, adalah daya kritis atas khazanah intelektual sebelumnya, kemampuan
sintesis berbagai varian intelektual yang luas, pembangunan argumentasi yang solid
dalam melahirkan pernyataan, dan kemampuan membangun identitas keilmuan
mandiri yang sesuai dengan tradisi intelektual, keagamaan, dan budaya Nusantara.
Dari para pengkaji dan pelanjut gagasan Mullâ Sadrâ di tanah kelahirannya, perlu
diambil sikap apresiatif terhadap gagasan pemikiran bangsa sendiri, khususnya
tentang cara mengapresiasi warisan pemikiran Hamzah Fansûrî dan pengikut
Wujudiah lainnya.
Dari Wujudiah Hamzah Fansûrî sangat banyak kandungannya yang dapat
menawarkan nilai aksiologis yang dapat dijadikan acuan nilai dalam mengatasi
berbagai problematika kontemporer, seperti basis intelektuai Islam Nusantara, basis
nilai pendidikan, dan sebagainya. Ajaran ini juga pernah menjadi tawaran dalam
menyelesaikan berbagai persoalan di Nusantara pada masa sebelumnya karena
memang sangat sesuai bagi tradisi keberagamaan dan kebudayaan masyarakat. Di
Kepulauan Indonesia, ajaran Wujudiah diketahui, antara lain, berasal dari karya
seorang 'arif dari India, Muhammad Fahl Allah al-Buhanpurî (m. 120 M) berjudul
Tuhfah al-Mursalah ila al-Ruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam (Tuhfah)36. Karya
itu disebarkan oleh Mufti Besar Kesultanan Aceh Darussalam, Syaikh Syams al-Dîn
al-Sumatranî37 (m. 1630 M). Tetapi sebelumnya, Syaikh Siti Jenar dan Hamzah
34 Al-Attas,Syed Muhammad Naquib, Islam dan Sejarah Kebudayaan Melayu
(Bandung: Mizan, 1990), 38. 35 Shainuddin Ali ibn Muhammad Al-Turkah, Sayyid Yadullah Yazdan Panah, dan
Hasan Mu’allimi adalah para filosof Sadrian yang berpandangan bahwa filsafat Mulla Sadra
itu identik atau setidaknya integral dengan Wahdah alWujud. Lihat, Jabir, Muhammad Nur,
Wahdah Al-Wujûd Ibn ‘Arabî Dan Filsafat Wujûd Mulla Sadrâ. (Makassar: Chamran Press),
2012, 17–18. 36 Arifin, Miftah “Tuhfah Al-Mursalah: Studi Terhadap Pemikiran Martabat Tujuh Al-
Burhanpury,” AL-’Adalah 7, no. 2 (2004): 41–52. 37 Nur, “Kritik Terhadap Pemikiran Tasawuf Al-Raniri.”, 137
18
Fansûrî telah mengajarkan ajaran tersebut. Tasawuf bercorak Wujudiah bahkan telah
berkembang sejak Kesultanan Peureulak38 dan Samudra Pasai39.
Meskipun tasawuf Wujudiah dinisbahkan kepada nama besar Ibn 'Arabî, tetapi
mazhab itu telah berkembang melalui sufi yang hidup jauh sebelum sufi dari Murcia
itu40. Sufyân al-Tsaurî (715–778 M), Syaikh Junayd al-Baghdadî (830–910 M), Abû
Mansûr al-Hallaj, dan Khâjâ ‘Abd Allah al-Anshârî (1006–1088 M) adalah sebagian
dari nama sufi41 yang telah mengajarkan tasawuf yang bercorak filosofis itu.
Demikian juga di Indonesia, tasawuf filosofis telah diajarkan oleh sufi sebelum
Syams al-Dîn al-Sumatranî, seperti Syaikh Siti Jenar dan Hamzah Fansûrî. Ciri ajaran
mazhab ini telah tersebar di Kepulauan Indonesia sejak jauh sebelum Kerajaan Aceh
Darussalam42. Bahkan, ajaran tasawuf filosofis kemungkinan menjadi pendekatan
pertama masuknya Islam ke Indonesia43.
Teologi (kâlâm), filsafat, dan tasawuf filosofis memiliki basis epistemologi
yang berbeda44. Basis epistemologi teologi adalah wahyu45. Al-Qur’an dan hadis
adalah fondasi utama bagi kâlâm. Filsafat memiliki basis utama berupa epistemologi
rasional. Akurasi logika dan silogisme adalah fondasi bagi filsafat46. Basis utama
epistemologi tasawuf filosofis adalah pengalaman langsung (hudhūrî atau
pengetahuan presentasi)47 yang hadir dengan dianalogikan seperti kilatan cahaya48.
Kalaupun kâlâm terkadang menggunakan logika dan hudhûrî, tetapi itu hanya
digunakan sejauh integratif dengan basis epistemologinya, yaitu wahyu. Demikian
juga filsafat terkadang menggunakan wahyu dan pengetahuan presentasi sebagai
bagian argumentasinya, tetapi dimaknai dalam bentuknya yang relevan dengan basis
epistemologinya, yaitu rasio. Tasawuf filosofis juga menggunakan wahyu dan rasio,
tetapi itu ditafsirkan secara eksoteris sehingga integral dengan pengetahuan
presentasi. Sementara ajaran Mullâ Sadrâ sendiri tidak bisa serta-merta digolongkan
sebagai ajaran tasawuf karena gagasan-gagasan yang dibangun menggunakan kaidah
38 Nasution, Ismail Fahmi Arrauf, dan Miswari, “Rekonstruksi Identitas Konflik
Kesultanan Peureulak,” Paramita 27, No. 2 (2017): 168–181. 39 Hasjmy, Ali, Nusantara, Syi’ah Dan Ahlussunnah Saling Rebut Pengaruh Dan
Kekuasaan Sejak Awal Sejarah Islam Di Kepulauan (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), 1-2. 40 Corbin, Henry, Creative Imagination in the Sufism of Ibn Arabi (Princeton: Princeton
Legacy Library, 2014), 39-40. 41 Urafâ adalah sebutan bagi kaum sufi aliran tasawuf falsafi atau disebut Wujudiah
dalam istilah Melayu. 42 Ismail Fahmi Arrauf Nasution, dan Miswari,, “Rekonstruksi Identitas Konflik”…,
168–181. 43 Kersten Amstrong, A History of Islam In Indonesia, 41. 44 Ismail Fahmi Arrauf Nasution, “Mencerna Akar Filsafat Dalam Islam,” Ulumuna
17, no. 1 (November 8, 2017): 1–18, http://ulumuna.or.id/index.php/ujis/article/view/236. 45 Harun Nusution, Teologi Islam (Jakarta: UIP, 2006), 99. 46 Abdul Hadi Fadli, Logika Praktis (Jakarta: Sadra Press, 2016), 3. 47 Mehdi Haeri Yazdi, The Principles of Epistemology in Islamic Phlosophy:
Knowledge by Presence (New York: State University of New York Press, 1992), 14. 48 Benny Susilo, “Teori Gradasi : Komparasi Antara Ibn Sînâ, Suhrawardi dan Mulla
Sadra,” Kanz Philosophia : A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism 5, no. 2
(December 29, 2015): 159,
http://journal.sadra.ac.id/index.php/kanzphilosophia/article/view/139.
19
penalaran filsafat. Ajaran itu merupakan sebuah revolusi penting dalam filsafat
karena Mullâ Sadrâ mengakui landasan pengetahuan yang dia bangun adalah
berdasarkan ilmu hudhūrî yang mana sistem itu biasanya digunakan dalam tasawuf
filosofis. Pertanyaan pentingnya adalah, bahkan antar pemikir dalam varian
pemikiran yang sama, banyak yang memiliki landasan paham ontologi yang berbeda.
Namun, meski berasal dari varian pemikiran yang berbeda, yakni Hamzah Fansûrî
merupakan sufi Wujudiah, sementara Mullâ Sadrâ merupakan seorang filosof,
mengapa keduanya memiliki keidentikan dalam dasar ontologi masing-masing, yakni
menerima wujûd sebagai univokal dan menjadi dasar realitas.
Ajaran tasawuf filosofis tertentu oleh sebagian pemikir dianggap sebagai
ajaran yang sesat dan menyesatkan49. Klaim tersebut, antara lain, muncul akibat
kesalahpahaman dalam memaknai pendekatan epistemologis yang digunakan
seorang pengajar Wujudiah50. Padahal, ajaran-ajaran mereka sangat berguna dan
dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan banyak masalah kontemporer di
Indonesia51. Karya Wujudiah di Indonesia yang oleh sebagian sarjana telah mampu
ditawarkan sebagai alternatif tetap saja kurang menarik perhatian publik akibat
stigma mendasar terhadap tasawuf filosofis. Karena pandangan demikian, sebagian
peneliti telah mencoba menawarkan ajaran Wujudiah, seperti dari pemikiran Hamzah
Fansûrî untuk diambil nilai aksiologisnya dalam rangka menawarkan alternatif bagi
berbagai persoalan kontemporer52. Pengkajian terus-menerus terhadap ajaran
Wujudiah sangat penting untuk menghadirkan nilai aksiologis bagi masyarakat.
Namun sayangnya karena sifat spekulatif ajaran tersebut membuatnya sangat jarang
mendapatkan perhatian sebagai bagian atau alternatif rujukan untuk menyelesaikan
problem-problem kontemporer yang dihadapi masyarakat Indonesia dan dunia.
Peneliti sangat yakin bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Wujudiah dapat
menjadi solusi untuk mengatasi problematika kontemporer.
Demikian juga filsafat Mullâ Sadrâ meskipun lahir dari tradisi yang berbeda
dengan masyarakat Indonesia, nilai-nilai positifnya dapat diambil oleh tradisi ilmiah
kita untuk memperkaya perspektif ilmu pengetahuan. Dari apresiasi masyarakatnya
atas tradisi filsafat mereka, kita juga dapat belajar tentang bagaimana menghargai dan
menghidupkan kembali warisan tradisi ilmu pengetahuan kita, seperti kekayaan
ajaran Hamzah Fansûrî.
Wujudiah selalu menjadi objek kajian yang menarik karena misteri ajarannya
hingga hari ini belum tuntas. Ajaran ini juga masih menjadi minat besar para peneliti
karena dapat dianalisis melalui berbagai perspektif. Syaikh Abd Jalîl dan Maharaja
Bakoy disebutkan sebagai tokoh awal Indonesia yang menyebarkan ajaran Wujudiah
v 50 Miswari, “Filosofi Komunikasi Spiritualitas: Huruf Sebagai Simbol Ontologi Dalam
Mistisme Ibn ’Arabî,” Al-Hikmah 9, no. 14 (2017): 12–30. 51 Nasution, “Humanisasi Pendidikan Islam Melalui Antropologi Transendental
Hamzah Fansûrî.”…, 235. 52 Ismail Fahmi Arrauf Nasution, “Termination of Wahdatul Wujud In Islamic
Civilization In Aceh: Critical Analysis of Ithaf Ad-Dhaki, The Works of Ibrahim Kurani,”
ADDIN 11, no. 2 (August 1, 2017): 401,
http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/view/3356.
20
pada masa Kesultanan Samudra Pasai53. Di Pulau Jawa, Syaikh Siti Jenar dianggap
sebagai penyebar Wujudiah. Meskipun prinsip-prinsip ajarannya telah eksis sejak
lama, ajaran Wujudiah baru dirumuskan secara sistematis oleh Ibn 'Arabî. Ajaran
tersebut memengaruhi banyak sufi setelahnya, termasuk ‘Abd al-Karîm al-Jîlî (1365–
1424 M) dan Fadh Allah al-Burhânpûrî. Ajaran Martabat Tujuh Fadh Allah al-
Burhânpûrî diajarkan dan disebarkan di Indonesia.
Dalam Wujudiah, tidak ada keberagaman. Selain wujûd hanya ada bayangan
yang sifatnya wahmî. Oleh para pengikutnya, Wujudiah diterima sebagai
kesempurnaan tauhid: memurnikan Allah dari segala sesuatu apa pun, hanya
menerima satu wujûd yang tunggal. Namun oleh sebagian mutakallimîn, Wujudiah
dianggap sebagai kesesatan. Alasannya karena mereka mengira Wujudiah adalah
ajaran yang beriktikad bahwa makhluk-makhluk di alam juga diakui sebagai Tuhan.
Padahal, dengan tegas Wujudiah hanya menerima satu wujûd yang dinisbahkan
kepada Haqq Ta’ala. Sementara selain itu hanyalah bayangan54.
Sementara itu, oleh sebagian sufi akhlak, Wujudiah dianggap tidak memiliki
argumentasi yang baik. Premis-premis untuk menjustifikasi Wujudiah dianggap
kurang sempurna. Sebagian orientalis pengkaji tasawuf, seperti W. T. Stace juga
mengatakan bahwa ajaran Wujudiah itu paradoks dan berseberangan dengan prinsip-
prinsip logika. Oleh sebab itulah, Wujudiah perlu terus-menerus diteliti, perlu juga
dibantu oleh ilmu lainnya untuk memperjelas ajarannya55. Hari ini setiap bidang ilmu
memang telah diakui tidak dapat menyelesaikannya dengan benar-benar tuntas. Hari
ini telah dimaklumi satu bidang ilmu perlu dipakai untuk membantu ilmu-ilmu
lainnya, atau membantu justifikasi56. Sebab itulah, kajian miltidisipliner menjadi
perhatian serius para peneliti dan pemikir.
Wujudiah memang merupakan suatu disiplin keilmuan khas tasawuf falsafi
(‘irfân). Seharusnya keilmuan yang terdekat dengan tasawuf falsafi adalah tasawuf
akhlak atau tasawuf amal. Namun sayangnya, keilmuan itu sering berseberangan dan
sering menentang Wujudiah serta iktikad-iktikad lainnya dari tasawuf falsafi karena
memang prinsipnya sangat berseberangan. Tasawuf akhlak atau tasawuf amal
mengusung prinsip prinsip wujûd sebagai ekuivokal. Sementara Wujudiah
mengusung prinsip wujûd sebagai univokal. Prinsip pandang wujûd ini memang
menjadi landasan begitu berseberangannya Wujudiah dengan tasawuf akhlak atau
tasawuf amal. Demikian juga filsafat Mullâ Sadrâ mengusung prinsip wujûd sebagai
univokal. Secara umum filsafat Mullâ Sadrâ digolongkan sebagai bagian dari ajaran
filsafat. Namun, tidak sedikit pemikir yang menggolongkannya sebagai varian
tasawuf filosofis karena keidentikan prinsip ontologinya dengan Wujudiah. Hamzah
Fansûrî dan Mullâ Sadrâ mengakui bahwa wujûd itu adalah sebuah kata yang hanya
53 Ali Hasjmy, Ruba’i Hamzah Fansûrî…, 1. 54 Nasution, “Termination of Wahdah al-Wujûd In Islamic Civilization In Aceh:
Critical Analysis of Ithaf Ad-Dhaki, The Works of Ibrahim Kurani.”, 401. 55 Walter Terence Stace, Mysticism and Philosophy (L.A.: Jeremy P. Tracher, 1980),
252–253. 56 M. Amin Abdullah, “Religion, Science, and Culture: An Integrated, Interconnected
Paradigm of Science,” Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies 52, no. 1 (April 8, 2015): 175,
http://aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/30.
21
memiliki acuan tunggal. Keidentikan ini membuat kajian Wujudiah dan filsafat Mullâ
Sadrâ memiliki keunikan untuk sebuah pembingkaian sebagai bagian dari syarat
dilakukan kajian perbandingan.
Adapun ajaran Wujudiah Hamzah Fansûrî menjadi sangat berbeda secara
prinsipiel dengan al-Hikmah al-Masyâ'iyyah meskipun mengakui wujûd sebagai
dasar realitas eksternal. Akan tetapi, aliran filsafat yang dinisbahkan kepada nama
besar Ibn Sînâ ini membedakan antar-wujûd pada setiap mâhiyah. Maka dari itu,
setiap wujûd yang berbeda itu sebenarnya adalah wujûd yang bercampur dengan
mâhiyah57. Sementara al-Hikmah al-Isyrâqiyyah sebagaimana pernyataan
pendirinya, Syihab al-Dîn al-Suhrawardî, menerima bahwa hanya Allah satu-satunya
Wujûd Mutlak. Akan tetapi dalam merumuskan filsafatnya, Syihab al-Dîn al-
Suhrawardî menjadikan mâhiyah sebagai dasar realitas eksternal, sementara wujûd
hanya menjadi konsep sekunder yang dapat menjadi tambahan bagi semua konsep
mâhiyah. Pandangan Syihab al-Dîn al-Suhrawardî tentunya bertentangan dengan
mutlak Wujudiah karena yang diterima Wujudiah adalah wujûd yang mendasar dan
tunggal, bukan kemendasaran mâhiyâh sebagaimana pandangan al-Hikmah al-
Isyrâqiyyah58. Wujudiah juga berbeda jauh dengan al-Hikmah al-Masyâ'iyyah karena
al-Hikmah al-Masyâ'iyyah berpendapat wujûd itu majemuk pada realitas eksternal.
Dan tentu berbeda dengan Wujudiah yang memandang wujûd itu tunggal. Maka dari
itu, yang secara umum memiliki kedekatan dengan Wujudiah filsafat Mullâ Sadrâ59.
Menjadi menarik menganalisis pemikiran Hamzah Fansûrî juga setidaknya
karena dua alasan. Pertama, karena dewasa ini perlu menemukan berbagai perspektif
dalam mengenal Tuhan. Pengenalan Allah melalui Wujudiah dapat membuat kaum
muslim lebih toleran. Hal ini dapat dipahami karena Wujudiah menggunakan
pendekatan objektif dalam rangka memperkenalkan Allah kepada umat Islam.
Pendekatan demikian menghindarkan dari persaingan antar aliran untuk dan tidak
menyudutkan aliran tertentu. Apabila pandangan metafisika Hamzah Fansûrî dapat
dihidupkan kembali, akan terbuka kemungkinan pemikiran Hamzah Fansûrî dapat
diterima sebagai alternatif bagi umat manusia, khususnya umat Islam dalam
mengenal Allah. Penulis optimis pengenalan Tuhan melalui tasawuf falsafi tidak
mengusung prinsip superioritas bagi aliran dan agama tertentu dalam mengenal
Tuhan. Oleh karena itu, mengenal Tuhan dalam pandangan demikian tidak akan
memunculkan egoisme bagi aliran tertentu. Cara tersebut dapat memberikan
harmonisasi antarumat beragama. Inilah yang dibutuhkan umat Islam dan semua
masyarakat Indonesia yang majemuk60.
Kedua, sekalipun kaum intelektual Nusantara, seperti Nûr al-Dîn al-Ranîrî,
Abd al-Rauf al-Sinkilî (1615–1693 m), dan ‘Abd al-Samad a-Falimbanî (1704–1789
57 Hanafi, Filsafat Islam, 126. 58 Muslih, “Kesadaran Intuitif Plus Cahaya Ilahiyah: Husserl Di Muka Cermin
Suhrawardi.” 59 Mohammed Rustom, “Knowledge in Later Islamic Philosophy: Mullā Ṣadrā on
Existence, Intellect, and Intuition,” Iranian Studies 45, no. 3 (May 2012): 457–461,
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00210862.2012.655066. 60 Mawardi, “Reaktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Kemajemukan
Sosial,” Substantia 17, no. April (2015): 55–66.
22
M) membuka ruang permisif pada taraf tertentu kepada sufi Wujudiah, seperti Ibn
'Arabî, ‘Abd al-Karim Al-Jîlî, dan Fadhl Allah al-Burhânpûrî61, ruang itu tidak ada
untuk Hamzah Fansûrî. Padahal, para cendikiawan sepakat bahwa varian pemikiran
Hamzah Fansûrî termasuk dalam Wujudiah sebagaimana dianut oleh Ibn 'Arabi, ‘Abd
al-Karim Al-Jîlî, dan Fadhl Allah al-Burhânpûrî62. Oleh karena itu, terdapat
kemungkinan bahwa terkandung sebuah misteri dalam ajaran Hamzah Fansûrî
sehingga tidak diberi sedikit pun ruang permisif sebagaimana penganut Wujudiah
lainnya. Padahal, bila dapat diobjektifkan, pemikiran Hamzah Fansûrî dapat
ditawarkan sebagai alternatif untuk mengatasi masalah-masalah kontemporer yang
dihadapi masyarakat Indonesia63.
Di samping ‘Abd al-Samad a-Falimbanî yang tidak merekomendasikan karya
Hamzah Fansûrî, tetapi merekomendasikan karya Ibn Arabî64, juga mengingat di
dalam Hujjat, Nûr al-Dîn al-Ranîrî memasukkan Ibn 'Arabî sebagai pengikut
Wujudiah. Disebutnya, Wujûdiyah muwahidah, yang artinya pengikut Wujudiah
yang benar, tidak sesat dan di dalam Tibyan fi Ma’rifah al-Adyan (Tibyan)’
menghujat Hamzah Fansûrî dan mengeklaim ajarannya sebagai Wujudiah mulhid
(sesat). Maka dari itu, dapat diasumsikan terdapat perbedaan antara pemikiran
Hamzah Fansûrî dan Ibn 'Arabî. Pemikiran Hamzah Fansûrî menjadi makin misterius
mengingat para cendekiawan kontemporer, seperti Drewes65, Naquib Al-Attas66, dan
Abdul Hadi WM67 memberikan pandangan positif terhadap pemikiran Hamzah
Fansûrî.
Pada sisi lain, pemikiran Mullâ Sadrâ menjadi menarik untuk dianalisis
setidaknya juga karena dua alasan. Pertama, ajaran tersebut tampak sangat netral dan
hanya berorientasi filofis ilmiah sehingga berpeluang tidak mengusung pretensi lain
selain daya filosofisnya sehingga layak dikaji untuk ditemukan kandungan positif
dalam ajaran filsafatnya. Kedua, ajaran tersebut merupakan kajian ketuhanan yang
bercorak sangat filosofis sehingga dapat menunjukkan perspektif kosmologis yang
berbeda dengan tradisi di Nusantara sehingga dapat menawarkan wawasan baru
dalam memahami bagaimana perspektif ketuhanan filosofis dipahami dalam tradisi
yang berbeda.
61 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama: Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad
XVII & XVIII (Jakarta: Kencana, 2013), 232-233. 62 Riddell, “Breaking the Hamzah Fansuri Barrier: Other Literary Windows into
Sumatran Islam in the Late Sixteenth Century CE”, 125-140; Zulkarnain Yani, “Analisis
Tematik Terhadap Syair Burung Pingai Karya Hamzah Fansuri,” Penamas Balai Litbang
Agama Jakarta XXII, no. Tema-Tema Sufistik (2009): 20. 63 Miswari, “Mu‘ḍilat Al-Aqlīyah Al-Masīḥīyah Fī Ḥudūd Balad Al-Sharī‘ah Al-
Islāmīyah,” Studia Islamika (August 2018), 351. 64 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama: Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad
XVII & XVIII…, 316. 65 Drewes, G.W.J., dan Brakel, L.F., The Poems of Ḥamzah Fansûrî (Dordetch: Forish
Publication Holland, 1986),1-3 . 66 Syed Muhammad Naquib Al-Attas, A Commentary on the Hujjat Al-Shiddiq of Nûr
Al-Dîn Al-Ranirî (Kuala Lumpu: Kuala Lumpu, 1986), 1-7. 67 Abdul Hadi W.M , Tasawuf Yang Tertindas: Kajian Hermeunetik Terhadap Karya
Hamzah Fansuri (Jakarta: Paramadina, 2001), 243.
23
Keidentikan landasan ontologis antara Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ dapat
dilacak pada pertemuannya dalam penyerapan yang mendalam atas skema filsafat
Neoplatonisme. Dalam Wujudiah sendiri, Neoplatonisme memang telah menjadi
skema dasar paradigma pemikirannya. Sistem-sistem hubungan ketunggalan dan
kemajemukan dalam Wujudiah, baik tajallî yang dirumuskan Ibn ‘Arabî maupun
ta’ayyûn yang dirumuskan Hamzah Fansûrî tidak dapat dipisahkan dari skema
emanasi dalam Neoplatonisme. Keidentikan ontologi Wujudiah Hamzah Fansûrî dan
filsafat Mullâ Sadrâ dapat saja dikatakan bermuara pada Ibn ‘Arabî. Keidentikan
pemikiran ajaran Hamzah Fansûrî dengan Ibn ‘Arabî mudah saja dipahami karena
Hamzah Fansûrî dengan setia mengikuti prinsip wahdat al-wujûd Ibn ‘Arabî.
Sementara Mullâ Sadrâ sendiri meskipun sebagai pemikir filsafat juga sangat banyak
menyerap pemikiran Ibn ‘Arabî. Meskipun demikian, Hamzah Fansûrî sendiri tidak
mudah diterima dibandingkan Ibn ‘Arabî. Sementara Mullâ Sadrâ sebagai seorang
filsuf masih sangat setia dengan prinsip penyusunan argumentasi dalam sistem
filsafat. Hal inilah yang membuat kajian perbandingan antara Wujudiah Hamzah
Fansûrî dan filsafat Mullâ Sadrâ menjadi menarik untuk dianalisis.
Kajian perbandingan menjadi lebih unik bila antar ajaran yang dianalisis
memiliki hubungan secara prinsipiel sekaligus memiliki perbedaan pada aspek-aspek
lainnya. Keunikan komparasi Wujudiah Hamzah Fansûrî dan filsafat Mullâ Sadrâ
karena secara prinsipiel keduanya menerima satu wujûd sebagai dasar realitas.
Sementara wujûd lainnya dalam kesatuan wujûd disebut sebagai wujûd yang
bergantung secara mutlak (mustaqil) pada wujûd yang satu dan mendasari realitas.
Sebagian pengikut Mullâ Sadrâ berpandangan bahwa gradasi (taskîk) wujûd dalam
filsafat Mullâ Sadrâ adalah tahapan untuk mengakomodir Wujudiah. Meskipun
sebagian pengikut Mullâ Sadrâ lainnya berpendapat bahwa inti filsafat Mullâ Sadrâ
adalah tâskîk al-wujûd, tidak dapat dimungkiri bahwa terdapat beberapa pernyataan
Mullâ Sadrâ yang dengan tegas menyatakan bahwa Wujûd Mutlak itu tunggal.
Namun, konsep Mullâ Sadrâ tentang basith basit al-haqîqah (hakikat sederhana) dan
imkan fakr (kefakiran akibat) adalah segala sesuatu makin mengarahkan pada
kedekatannya dengan Wujudiah68.
Di samping itu, masyarakat Melayu dan masyarakat Persia sama-sama
memiliki kecenderungan pada mistisme. Bedanya, masyarakat Persia juga gemar
dengan diskursus filsafat Aristotelian. Sementara tidak ditemukan catatan
perkembangan diskursus filsafat Aristotelian dalam masyarakat Melayu-Nusantara,
kecuali filsafat bercorak Neoplatonisme yang dielaborasi dalam ajaran mistisme
tasawuf Wujudiah69. Dengan demikian, antara Wujudiah Hamzah Fansûrî dan filsafat
Mullâ Sadrâ dapat ditemukan beberapa persamaan yang dapat membingkai kedua
pemikir besar itu. Pertama, mereka melakukan usaha sintesis ajaran-ajaran
sebelumnya. Bila Mullâ Sadrâ melakukan sintesis untuk mengintegrasikan hampir
semua khazanah pemikiran sebelumnya, Hamzah Fansûrî hanya berfokus pada
pengintegrasian mazhab pemikiran tasawuf Wujudiah sebelum dirinya. Kedua,
mereka menyadari konteks tradisi keilmuan dan budaya masing-masing sehingga
68 Syaifan Nur, Filsafat Hikmah Mulla Sadra…, 85. 69 Humaidi, “Mystical-Metaphysics: The Type of Islamic Philosophy in Nusantara in
the 17th-18th Century,” 90.
24
melakukan cara yang berbeda dalam menyampaikan ajaran asing-masing. Pada satu
pihak, Mullâ Sadrâ memilih cara yang rumit dan panjang lebar dalam menjelaskan
metafisikanya karena memungkinkan untuk konteks keilmuan dan budayanya.
Sementara Hamzah Fansûrî memilih menggunakan bahasa puitis dan analogi
sederhana untuk menjelaskan ajarannya karena menyesuaikan dengan konteks
masyarakat Melayu pada masa itu.
Ketiga, persamaan yang sangat penting untuk membingkai Wujudiah
Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ adalah keduanya mendiskursuskan tema esensial
dalam diskursus pemikiran Islam, yakni mengenai konsep Ilahiah secara filosofis.
Mereka juga sama-sama menerima kemendasaran wujûd yang mana diskursus wujûd
merupakan persoalan penting dalam metafisika. Antara lain, pembingkaian ini yang
membuat analisis ajaran Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ menjadi urgen dan
signifikan. Dari dua pemikir ini tentu mengandung sangat banyak kandungan sarat
nilai aksiologis guna menjadi basis filosofis sebagai tawaran penyelesaian berbagai
persoalan kontemporer. Semangat spiritual Hamzah Fansûrî dapat ditawarkan
sebagai basis solusi problem spiritualitas. Semangat intelektualitas Mullâ Sadrâ dapat
ditawarkan menjadi solusi mengatasi krisis intelektual dan penawaran langkah tepat
dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
Dengan berbagai persinggungan antara filsafat Mullâ Sadrâ dan Wujudiah
maka dalam penelitian ini perlu dianalisis secara khusus tentang komparasi filsafat
Mullâ Sadrâ dan penganut Wujudiah, yakni Mullâ Sadrâ. Pembahasan berikutnya,
yakni tentang komparasi dua tokoh pemikir ini menjadi bagian penting bagi
penelitian ini.
Penelitian ini memilih pemikiran Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ untuk
dianalisis secara komparatif. Di samping beberapa kemiripan antara keduanya, alasan
lainnya memilih Hamzah Fansûrî, antara lain, juga karena ditemukan banyak nilai
yang dapat ditawarkan untuk mengatasi problematika kontemporer70. Hanya saja,
ajaran Hamzah Fansûrî dikemas dalam sistem analogi sehingga membutuhkan sebuah
deskripsi yang lebih naratif untuk menjabarkan ajaran metafisika spekulatif yang
terkandung di dalam karya-karyanya71. Penulis melakukan kajian perbandingan
pemikiran Hamzah Fansûrî dengan ajaran Mullâ Sadrâ karena dua ajaran tersebut
berasal dari tradisi yang berbeda. Kajian perbandingan tentunya bukan untuk
menemukan kekurangan masing-masing, namun untuk menemukan persamaan dan
perbedaan dari tiap-tiap ajaran filosofis dari dua tradisi yang berbeda. Antara lain,
guna memberikan apresiasi yang lebih patut bagi ajaran penting dari tradisi
intelektualitas Indonesia.
70 Misalnya menjadi fondasi humanisasi pendidikan Islam, menjadi landasan ontologis
kajian Islam Nusantara, menjadi landasan aksiologis, lihat, Nasution, “Humanisasi
Pendidikan Islam Melalui Antropologi Transendental Hamzah Fansûrî”, 235; Kamaruzzaman
Bustamam-Ahmad, Kontribusi Charles Taylor, Syed Muhammad Naquib Al-Attas, dan Henry
Corbin Dalam Studi Metafisika & Meta Teori Terhadap Islam Nusantara Di Indonesia
(Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), 204; Ramli Cibro, Aksiologi Ma’rifat Hamzah
Fansuri (Banda Aceh: Pade Books, 2017), 137. 71 Zakaria, “Dakwah Sufistik Hamzah Fansuri: Kajian Substantif Terhadap Syair
Perahu,” Jurnal Ilmiah Islam Futura 13, no. 1 (2013): 105–125.
25
Diharapkan juga agar ajaran Wujudiah Hamzah Fansûrî dapat disertakan dalam
berdiskusi secara seimbang dalam diskursus pemikiran Islam. Semangat ini, antara
lain, dapat dibangun melalui semangat ajaran Mullâ Sadrâ yang oleh pendukungnya
dianggap telah mampu menyintesis banyak aliran pemikiran Islam, dari kâlâm,
tasawuf, hingga aliran-aliran filsafat sebelumnya, khususnya Peripatetik Islam (al-
Hikmah al-Masya'iyyah)72 dan Illuminasionisme Islam (al-Hikmah al-Isyraqiyyah)73.
Singkatnya, Mullâ Sadrâ telah mampu menganalisis hampir semua aliran pemikiran
Islam dalam sebuah aliran filsafat baru yang dinamakan al-Hikmah al-Muta'alliyah74.
Melalui semangat Mullâ Sadrâ ini, setidaknya dapat memberikan sebuah gambaran
untuk mengharmoniskan berbagai tradisi pemikiran Islam yang berkembang di
Indonesia, termasuk mengharmoniskan ajaran perdebatan ajaran kâlâm dan Wujudiah
Hamzah Fansûrî.
Hamzah Fansûrî telah menulis banyak karya, di antaranya berbentuk syair dan
prosa. Syair-syairnya telah dikumpulkan dan dianalisis oleh berbagai sarjana. Paling
kurang terdapat tiga puluh syair yang ditulis dalam bentuk ruba'i. Sementara karya
prosanya berjumlah tiga judul, yaitu Asrâr al-‘Arifîn (Asrâr), Syarâb al-Asyîqîn
(Syarâb) dan al-Muntahî75. Asrâr adalah penjelasan Hamzah Fansûrî sendiri terhadap
syair ruba'i-nya. Di samping itu, Syams al-Dîn al-Sumatranî juga telah menganalisis
ruba'i Hamzah Fansûrî dan telah diterbitkan di Malaysia dan diberi transliterasi oleh
Ali Hasjmy76. Sementara Mullâ Sadrâ telah menulis sekitar empat puluh judul karya.
Di antaranya adalah al-Hikmah al-Muta'alliyah fi al-Asfar ‘Aqliyah Arba’ah yang
biasa disingkat dengan Asfar.
Tiap-tiap pemikiran antara Hamzah Fansûrî dan filsafat Mullâ Sadrâ menjadi
minat bagi sebagian peneliti filsafat dan tasawuf. Pada periode klasik, Shams al-Dîn
al-Sumatranî telah meneliti dan mensyarah syair Ruba’i Hamzah Fansûrî dengan
penjelasan yang bersifat esensial, yakni fokus untuk menerangkan secara ringkas dan
padat setiap baris Ruba’i77. Sementara itu, pemikiran Mullâ Sadrâ telah diteliti dan
diringkas gagasan-gagasan utamanya dalam bahasa yang amat puitis oleh Mullâ Hâdî
Sabzawârî (1797–1873).
72 A. Khudori Soleh, “Mencermati Sejarah Perkembangan Filsafat Islam,” TSAQAFAH
10, no. 1 (May 31, 2014): 63,
http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/64. 73 Kerwanto, “Manusia Dan Kesempurnaannya (Telaah Psikologi Transendental Mullā
Shadrā),” Kanz Philosophia : A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism 5, no. 2
(December 20, 2015): 133,
http://journal.sadra.ac.id/index.php/kanzphilosophia/article/view/136. 74 Ibrahim Kalin, Knowledge in Later Islamic Philosophy, Knowledge in Later Islamic
Philosophy: Mulla Sadra on Existence, Intellect, and Intuition (Oxford: Oxford University
Press, 2010), 12,
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199735242.001.0001/acpr
of-9780199735242. 75 Asrâr al-‘Arifîn selanjutnya disebut Asrâr, Syarâb al-Asyiqîn' selanjutnya disebut
Syarab, dan al-Musammâ bî al-Muntahî' selanjutnya disebut al-Muntahî'. 76 Ali Hasjmy, Ruba’i Hamzah Fansuri…, 1-3. 77 Ali Hasjmy, Ruba’i Hamzah Fansuri…,
26
Penelitian atas pemikiran Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ menjadi sangat
berkembang sejak abad kedua puluh. Di antara penelitian penting dilakukan oleh
Johan Doorenbos, Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Drewes dan Brakel, Vladimir
Braginsky, dan Abdul Hadi WM. Sebagai salah satu di antara perintis penelitian
modern atas pemikiran Hamzah Fansûrî, Johan Doorenbos telah memberikan
sumbangan besar bagi khazanah ilmu pengetahuan dalam menghidupkan kembali
pemikiran khasik dengan melakukan transliterasi atas prosa-prosa dan syair-syair
Hamzah Fansûrî78. Penelitian tersebut sangat membantu memudahkan peneliti
modern dalam memahami pemikiran Hamzah Fansûrî untuk tahap selanjutnya. Syed
Muhammad Naquib Al-Attas melanjutkan usaha Johan Doorenbos dengan fokus
pada gaya transliterasi yang lebih modern pada prosa-prosa Hamzah Fansûrî. Tidak
hanya itu, Syed Muhammad Naquib Al-Attas juga melakukan analisis mendalam atas
pemikiran metafisika Hamzah Fansûrî berdasarkan istilah-istilah penting dari
pemikirannya79. Hasil penelitian Syed Muhammad Naquib Al-Attas telah
memudahkan peneliti selanjutnya dalam memahami pokok pemikiran metafisika
Hamzah Fansûrî. Di samping itu, pemikiran-pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-
Attas sendiri tentang keagamaan, kebudayaan, dan pendidikan sangat dipengaruhi
oleh pemikiran Hamzah Fansûrî.
Penelitian Drewes dan Brakel atas pemikiran Hamzah Fansûrî fokus pada
transliterasi atas puisi-puisinya yang terdapat di beberapa museum di Eropa, seperti
Inggris dan Belanda. Penelitian-penelitian selanjutnya dari Drewes dan Brakel terkait
dengan kajian agama di Asia Tenggara hampir tidak pernah melewatkan ulasan atas
pemikiran Hamzah Fansûrî. Sementara itu, Vladimir Braginsky meneliti tentang puisi
Hamzah Fansûrî khususnya “Syair Perahu”80 tentang Adapun Abdul Hadi WM juga
telah meneliti dan mentransliterasi syair-syair Hamzah Fansûrî dengan jumlah yang
sangat lengkap. Dalam karya ini juga disertakan terjemahan dari bahasa-bahasa
Melayu yang sulit, bahasa Arab dan bahasa Persia. Maka dari itu, makna syairnya
dapat dipahami dengan baik. Setidaknya ada sekitar tiga puluh dua syair yang telah
dihadirkan81.
Kajian atas pemikiran Hamzah Fansûrî beserta penjelasan atas penentangan
Nûr al-Dîn al-Ranîrî juga dibahas oleh peneliti yang kompeten, seperti Vladimir
Braginsky, Syed Muhammad Naquib Al-Attas, dan Drewes dan Brakel. Oleh sebab
itu, penelitian ini tidak akan berfokus pada diskursus dua pemikir Melayu tersebut,
kecuali pada aspek-asek yang terkait dengan fokus penelitian, yakni kajian
perbandingan ontologi antara Wujudiah Hamzah Fansûrî dan filsafat wujud Mullâ
Sadrâ.
78 Johan Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri (Leiden: Betteljee &
Terpstra, 1933), 5. 79 Syed Muhammad Naquib Al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansuri (Kuala
Lumpur: University of Malaya Press, 1970), 13. 80 Vladimir Braginsky, “Some Remarks on the Structure of the ‘Sya’ir Perahu’by
Hamzah Fansuri,” Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities
and Social Sciences of Southeast Asia 131, no. 4 (January 1, 1975): 407–426,
https://brill.com/abstract/journals/bki/131/4/article-p407_1.xml. 81 Abdul Hadi W.M,, Tasawuf Yang Tertindas: Kajian Hermeunetik Terhadap Karya
Hamzah Fansuri (Jakarta: Paramadina, 2001), 315.
27
Sementara penelitian atas pemikiran Mullâ Sadrâ telah dilakukan oleh sangat
banyak pemikir. Tidak terhitung jumlahnya. Dalam meneliti pemikiran Mullâ Hâdî
Sabzawârî, Toshihiko Izutsu telah melakukan kajian yang mendalam atas metafisika
Mullâ Sadrâ. Fazlur Rahman juga telah menulis dengan baik pemikiran Mullâ Sadrâ
dengan membandingkannya dengan para pemikir terdahulu, terutama Ibn Sînâ, Ibn
‘Arabî dan Syihab al-Dîn al-Suhrawardî82. Penelitian penting lainnya atas pemikiran
Mullâ Sadrâ dilakukan oleh Ibrahim Kalin yang meneliti tentang fakultas-fakultas
jiwa dalam pemikiran Mullâ Sadrâ 83.
Di Indonesia, setidaknya ada tiga penelitian penting atas pemikiran Mullâ
Sadrâ. Pertama dilakukan oleh Hasan Bakti Nasution di IAIN Syarif Hidayatullah
Jakarta di bawah bimbingan Mulyadhi Kartanegara dan Jalaluddin Rakhmat. Dalam
disertasi tersebut dikaji pembangunan filsafat Mullâ Sadrâ dengan menyintesis
berbagai varian pemikiran Islam sebelumnya84. Di Yogyakarta, Syaifan Nur telah
mengkaji filsafat wujûd Mullâ Sadrâ. Selanjutnya telah banyak artikel yang mengulas
pemikiran Mullâ Sadrâ. Khususnya jurnal Kanz Philosophia yang fokus pada artikel
filsafat Islam dan telah banyak memuat artikel tentang pemikiran Mullâ Sadrâ dalam
berbagai dimensi.
Kajian perbandingan filsafat yang sangat populer, antara lain, dilakukan oleh
Sir Muhammad Iqbal dalam penelitiannya tentang metafisika Persia. Dalam kajian
tersebut, dilakukan perbandingan antara Aristotelianisme dan Neoplatonisme,
monisme dan dualisme, materialisme, rasionalisme, dan sufisme yang memengaruhi
dan membentuk pemikiran metafisika di dunia Persia. Dalam kajiannya itu, Sir
Muhammad Iqbal hanya sedikit menyinggung pemikiran Mullâ Sadrâ85. Kajian
perbandingan pemikiran Mullâ Sadrâ dengan filsuf lainnya pernah dilakukan oleh
Arpaslan Achicgenk. Dia membandingkannya dengan Martin Heideggar. Namun,
penelitian tersebut menggunakan teori paralelisme sehingga hanya fokus pada
persamaan pemikiran dan pembangunan argumentasi antara wujûd Mullâ Sadrâ dan
Sein Martin Heideggar. Kajian perbandingan filsafat lainnya dilakukan oleh
Toshihiko Izutsu dalam menganalisis istilah kunci dalam filsafat Taoisme dan
sufisme Ibn ‘Arabi yang difokuskan pada karya Fusûs al-Hikâm. Dalam
penelitiannya itu, Toshihiko Izutsu menyadari perbedaan konteks kebudayaan antara
Taoisme dan sufisme. Karena itu, dia mengingatkan supaya konteks budaya sebagai
pembentuk pemikiran tiap-tiap filsufnya perlu diperhatikan. Penelitian ini berusaha
mengikuti peringatan tersebut sehingga kajian perbandingan Wujudiah Hamzah
Fansûrî dan filsafat Mullâ Sadrâ tidak mengabaikan konteks budaya dan
perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Melayu dan Persia. Penelitian ini
82 Fazlur Rahman, The Philosophy of Mulla Sadra (Sadr Al-Din Al-Shirazi),
Knowledge Creation Diffusion Utilization (New Jersey: State University of New York Press,
1975), 15. 83 Ibrahim Kalin, Knowledge in Later Islamic Philosophy, Knowledge in Later Islamic
Philosophy: Mulla Sadra on Existence, Intellect, and Intuition (Oxford: Oxford University
Press, 2010), 15, 84 Hasan Bakti Nasution, “Hikmah Muta’alliyah: Analisa Terhadap Proses Sintesa
Filosofis Mulla Sadra” (IAIN Jakarta, 2001), 25. 85 Allama Sir Muhammad Iqbal, Metafisika Persia: Suatu Sumbangan Untuk Sejarah
Filsafat Islam…, 121.
28
menunjukkan konteks masing-masing sangat memengaruhi pembentukan gagasan
dan nasib selanjutnya dari pemikiran tokoh yang menjadi fokus pembahasan.
Sebagaimana diperingatkan M. Amin Abdullah dalam mengkaji pemikiran etika
antara Abû Hamid al-Ghazalî dan Immanuel Kant, kajian perbandingan bersyarat
pada terdapatnya persamaan, perbedaan, dan konsekuensi pemikiran dari tiap-tiap
tokoh yang dikaji.
Dari semua penelitian yang telah dieksplorasi di atas, belum ditemukan
penelitian tentang kajian perbandingan pemikiran Hamzah Fansûrî dan filsafat Mullâ
Sadrâ. Namun dari berbagai penelitian itu, penulis sangat banyak mengambil sisi
pentingnya. Kajian tentang Hamzah Fansûrî oleh Shams al-Dîn al-Sumatranî sangat
membantu memahami syair-syair Hamzah Fansûrî yang sulit dipahami maknanya.
Demikian juga kajian dari Johan Doorenbos, Drewes dan Brakel, dan Abdul Hadi
WM sangat membantu memahami gagasan umum pemikiran Hamzah Fansûrî.
Kajian Abdul Hadi WM juga sangat membantu memahami konteks ajaran Hamzah
Fansûrî. Sementara kajian dari Syed Muhammad Naquib Al-Attas membantu
pemahaman tentang istilah kunci dalam gagasan metafisika Hamzah Fansûrî. Fokus
penelitian untuk karya Asrâr juga mengandalkan transliterasi dari Syed Muhammad
Naquib Al-Attas.
Pola pembangunan pemikiran pemikiran dan istilah-istilah penting dalam
pemikiran Mullâ Sadrâ turut dibantu oleh penelitian Fazlur Rahman, Hasan Bakti
Nasution, dan Syaifan Nur. Namun, dua karya ini merupakan kajian pemikiran Mullâ
Sadrâ generasi awal di Indonesia sehingga mengandung beberapa kelemahan yang
perlu diperbaiki dalam memahami gagasan pentingnya. Kajian Toshihiko Izutsu atas
metafisika Mullâ Hâdî Sabzawârî sangat membantu dalam menjelaskan sistem
ontologi Mullâ Sadrâ. Demikiran juga, penelitian Ibrahim Kalin dapat membantu
menjelaskan manifestasi wujûd dalam berbagai fakultas jiwa menurut sistem
pemikiran Mullâ Sadrâ. Namun demikian, argumentasi untuk istilah-istilah penting
dalam ontologi Mullâ Sadrâ tetap diusahakan merujuk pada karyanya yakni Asfâr dan
Masya’ir.
Kajian perbandingan yang dilakukan Sir Muhammad Iqbal dalam filsafat
Islam hanya fokus pada pemikiran filosof sebelum Mullâ Sadrâ sehingga semangat
yang banyak diambil dalam penelitian ini hanyalah untuk memahami latar belakang
perkembangan metafisika di Persia. Penelitian ini mengikuti kajian perbandingan M.
Amin Abdullah yang menekankan pada pembingkaian persamaan mendasar dan
penemuan aspek persamaan pemikiran antara dua tokoh yang dikaji86. Dalam
penelitan kajian perbandingan pemikiran Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ,
pembingkaian persamaannya adalah pemahaman dalam univokasi dan kemendasaran
wujûd dan berusaha menemukan perbedaan-perbedaan relevan terkait dengan fokus
penelitian. Penelitian ini juga mengikuti kajian perbandingan Toshihiko Izutsu yang
menekankan untuk tidak mengabaikan aspek budaya ilmu pengetahuan dan dimensi
86 M. Amin Abdullah, Antara Al-Ghazali Dan Kant: Filsafat Etika Islam (Bandung:
Mizan, 2002), 44.
29
sosial dalam tiap-tiap konteks pemikiran dua tokoh yang pemikirannya
diperbandingkan87.
Kajian perbandingan Arpaslan Achicgenk menggunakan teori paralelisme.
Kajian perbandingan demikian berfokus pada penemuan dimensi persamaan yang
sangat sempit, yakni paralelitas antara wujûd dan Sein88. Sementara penelitian ini
meskipun fokus pada kajian perbandingan wujûd, berusaha menemukan latar
belakang munculnya dimensi kesamaan serta implikasi sosiologis dari tiap-tiap ajaran
dari Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ. Penelitian ini menggunakan konsep relasi
dalam ilmu logika untuk memudahkan memahami model persamaan antara relasi
ekuivalen, relasi umum-khusus mutlak, dan relasi umum-khusus satu sisi. Sementara
relasi nonekuivalen adalah termasuk dimensi perbedaan antara ajaran Hamzah
Fansûrî dan Mullâ Sadrâ.
Penelitian yang berfokus pada pemikiran Hamzah Fansûrî dikhususkan dalam
kajian atas karya Asrâr karena pandangan-pandangan Hamzah Fansûrî dalam karya
itu bersifat sangat filosofis dan sistematis. Itu berbeda dengan karya-karya lainnya
dalam bentuk puisi yang sangat sulit dipahami. Karya Asrâr dapat dikatakan deskripsi
yang sangat jelas atas pemikiran Hamzah Fansûrî. Dengan demikian, hasil dari
penelitian atas karya tersebut dapat menentukan posisi pemikiran metafisika Hamzah
Fansûrî. Asrâr merupakan penjelasan Hamzah Fansûrî tentang Allah yang
disampaikan dengan cara yang unik. Analogi-analogi yang digunakan sangat
menarik. Asrâr mengandung sangat banyak kata yang dijadikan analogi yang
semuanya bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana Allah tentang relasinya
dengan makhluk dalam pandangan Hamzah Fansûrî sendiri. Asrâr merupakan karya
Hamzah Fansûrî yang bercorak sangat filosofis. Dengan demikian, penelitian ini
dapat dikatakan bersubjek pada penelitian atas landasan metafisika Hamzah Fansûrî.
Sementara fokus analisis terhadap pemikiran Mullâ Sadrâ adalah atas pokok-
pokok gagasannya, seperti kemendasaran wujûd (ashalat al-wujûd), gradasi wujûd
(tâskîk al-wujûd), kefakiran akibat dalam kausalitas (illiyah), hakikat sederhana
(basith al-haqîqah), gerak substansi (al-harakah al-jawhayiah), dan kesatuan subjek
dan objek (ittihad aqil wa ma’qûl) yang merupakan konsep penting dalam ajaran
Mullâ Sadrâ. Gagasan-gagasan tersebut sekaligus membuat ajaran filsafat Mullâ
Sadrâ menjadi tidak berjarak dengan tasawuf filosofis. Bahkan, sebagian sarjana
menganggap ajaran Mullâ Sadrâ memang merupakan bagian dari tasawuf filosofis
yang identik dengan Wujudiah. Keidentikan ajaran Mullâ Sadrâ dengan Wujudiah
membuat kajian komparasi Wujudiah Hamzah Fansûrî yang berfokus pada Asrâr dan
filsafat Mullâ Sadrâ yang bernuansa tasawuf filosofis menemukan pembingkaiannya.
Penelitian ini dimulai dengan mendeskripsikan perdebatan teoretik tentang
konsep wujûd dalam Wujudiah yang melibatkan Hamzah Fansûrî dan perdebatan
teoretik dalam filsafat yang melibatkan Mullâ Sadrâ. Selanjutnya, kajian narasi
87 Toshihiko Izutsu, Sufism and Taoism: A Comparative Study of Key Philosophical
Concepts (Berkeley, Los Ageles London: University of California Press, 1983), 15. 88 Alparslan Açıkgenç, Being and Existence in Ṣadrā and Heidegger: A Comparative
Ontology (Kuala Lumpur: ISCAC, 1993), 27–28.
30
singkat tentang karya-karya dari tiap-tiap tokoh yang diteliti. Kemudian,
menganalisis tentang Wujudiah Hamzah Fansûrî dan dilanjutkan dengan
menganalisis filsafat Mullâ Sadrâ. Setelah itu, melakukan analisis perbandingan
antara Wujudiah Hamzah Fansûrî dan filsafat Mullâ Sadrâ untuk menemukan
persamaan dan perbedaan dari ajaran dua pemikir besar tersebut.
Dari kajian di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi antara lain adalah
perbedaan pemahaman wujûd dalam berbagai varian pemikiran Islam, penolakan atas
pemikiran Wujudiah Hamzah Fansûrî dan penerimaan atas pemikiran Wujudiah Ibn
‘Arabî oleh mutakallimîn, konteks ajaran Wujudiah Hamzah Fansûrî dan konteks
ajaran filsafat Mullâ Sadrâ, kekayaan nilai aksiologis dalam Wujudiah Hamzah
Fansûrî dan filsafat Mullâ Sadrâ, perbedaan varian dalam pemikiran Hamzah Fansûrî
dan filsafat Mullâ Sadrâ, dan persamaan prinsip ontologi dalam Wujudiah Hamzah
Fansûrî dan filsafat Mullâ Sadrâ.
Dari beberapa masalah yang telah teridentifikasi, penelitian ini dibatasi pada
Wujudiah Hamzah Fansûrî yang merupakan ranah keilmuan tasawuf falsafi dan
ajaran Mullâ Sadrâ yang merupakan ranah keilmuan filsafat, namun memiliki
landasan ontologi yang nyaris identik.
Dari pembatasan masalah yang telah ditentukan maka perumusan masalahnya
adalah: bagaimana Wujudiah Hamzah Fansûrî dan Filsafat Mullâ Sadrâ bisa memiliki
landasan metafisika yang nyaris identik, bagaimana ajaran metafisika Hamzah
Fansûrî dan Mullâ Sadrâ, dan Apa saja persamaan dan perbedaan ajaran Hamzah
Fansûrî dan filsafat Mullâ Sadrâ?
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang keidentikan ajaran
ontologi Wujudiah Hamzah Fansûrî dan filsafat Mullâ Sadrâ, menganalisis ontologi
Wujudiah Hamzah Fansûrî dan filsafat Mullâ Sadrâ, dan menganalisis persamaan dan
perbedaan Wujudiah Hamzah Fansûrî dan filsafat Mullâ Sadrâ.
Penelitian ini sangat penting untuk menyingkap latar belakang ajaran, prinsip
ontologi, dan dampak dari tiap-tiap ajaran Wujudiah Hamzah Fansûrî dan filsafat
Mullâ Sadrâ. Lahirnya sebuah ajaran dari pemikir besar tentunya sangat dipengaruhi
oleh latar belakang sosial budaya dan karier intelektual pemikirnya. Dengan
demikian, menganalisis dan menyingkap latar belakang tersebut menjadi sangat
penting untuk memahami berbagai faktor pembentuk ontologi ajaran Hamzah Fansûrî
dan Mullâ Sadrâ. Demikian juga dampak dari pemikiran masing-masing tentu perlu
dipahami, antara lain, untuk memahami bagaimana kelanjutan ajaran tersebut dalam
konteks sosial budayanya masing-masing.
Pada satu sisi, ajaran Wujudiah Hamzah Fansûrî masih dianggap kontroversial
dalam konteks keberagamaan masyarakat. Padahal, ajaran tersebut memiliki
kandungan ajaran yang dapat berkontribusi menjadi basis nilai dalam mengatasi
berbagai problematika kontemporer. Sementara ajaran filsafat Mullâ Sadrâ memiliki
potensi untuk menyemangati perkembangan dunia ilmu pengetahuan.
Kedekatan ajaran Hamzah Fansûrî dan filsafat Mullâ Sadrâ berkontribusi untuk
melahirkan sebuah konsep keilmuan integratif antara Wujudiah dan filsafat.
Formulasi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan keilmuan.
Diharapkan gagasan ini dapat menjadi inspirasi pembangunan keilmuan yang kukuh.
Penelitian ini juga diharapkan dapat mewujudkan semangat atas penelitian-
penelitian tentang Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ, yang oleh para penelitinya
31
dianggap dapat memberikan sebuah alternatif bagi masalah-masalah kontemporer.
Dengan demikian, tawaran-tawaran dari para peneliti itu dapat dipahami secara
mudah.
Penelitian tentang Hamzah Fansûrî telah dilakukan oleh beberapa sarjana. Di
antaranya, Drewes dan Brakel meneliti puisi-puisi Hamzah Fansûrî yang terdapat di
berbagai museum dunia, khususnya di Inggris dan Belanda. Penelitian itu hanya
menggambarkan garis besar pemikiran Hamzah Fansûrî dan mentransliterasi puisi-
puisi itu dari aksara Jawi ke aksara Latin dan menerjemahkannya ke bahasa Inggris89.
Abdul Hadi WM meneliti puisi-puisi Hamzah Fansûrî yang tersimpan di
Museum Nasional Jakarta90. Penelitian ini menggunakan hermeneutika spiritual atau
ta’wil untuk membuat ajaran-ajaran Hamzah Fansûrî yang disampaikan melalui
bahasa puisi yang bersifat simbolik menjadi mudah dipahami. Penelitian ini berhasil
menyingkap makna-makna simbolis yang tersembunyi di balik syair-syair Hamzah
Fansûrî. Penelitian atas puisi Hamzah Fansûrî lebih lengkap oleh Abdul Hadi WM.
Doorenbos juga melakukan penelitian tentang puisi dan prosa Hamzah Fansûrî.
Dalam disertasi di Universitas Leiden tahun 1933 tersebut, Doorenbos hanya
memberikan sedikit keterangan tentang tiap-tiap syair Hamzah Fansûrî, lalu fokus
pada transliterasi latin dan terjemahan dalam bahasa Belanda atas syair-syair dan
prosa Hamzah Fansûrî dalam bahasa Belanda. Hasil transliterasi oleh Doorenbos
masih sulit diakses karena ditransliterasi ke dalam ejaan lama yang menyulitkan
pemahaman pembaca Indonesia-Melayu modern.
Syed Muhammad Naquib Al-Attas, mentransliterasi prosa-prosa Hamzah
Fansûrî yang tersimpan di Inggris dan Belanda91. Konsep-konsep kunci yang terdapat
dalam ajaran Hamzah Fansûrî, seperti konsep “wujûd”, “ada”, “diri”, dan sebagainya
dianalisis dengan menggunakan pendekatan semantik. Al-Attas dalam penelitian ini
menguraikan konsep-konsep kunci tersebut dengan sangat detail.
Vladimir Braginsky juga termasuk peneliti serius pemikiran Hamzah Fansûrî.
Dia telah menuliskan banyak karya tentang syair-syair Hamzah Fansûrî92. Vladimir
Braginsky juga banyak meneliti tentang pemikiran Hamzah Fansûrî93. Dia juga telah
menulis riwayat kehidupan Hamzah Fansûrî94.
89 Drewes dan Brakel, The Poems of Ḥamzah Fansûrî…, 42-43. 90 Abdul Hadi W.M., Tasawuf Yang Tertindas: Kajian Hermeunetik Terhadap Karya
Hamzah Fansuri,190-191. 91 Al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansuri, xiii-xiv. 92 Yang Indah, Berfaedah dan Kamal: Sejarah Sastra Melayu Dalam Abad 7-19
(Jakarta: INIS, 1998), 508-509. 93 Vladimir Braginsky, “Some Remarks on the Structure of the ‘Sya’ir Perahu’by
Hamzah Fansuri,” Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities
and Social Sciences of Southeast Asia 131, no. 4 (January 1, 1975): 407–426,
https://brill.com/abstract/journals/bki/131/4/article-p407_1.xml. 94 Vladimir Braginsky, Satukan Hangat dan Dingin: Kehidupan Hamzah Fansuri
Pemikir dan Penyair Sufi Melayu (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003).
32
Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad melakukan penelitian tentang metateori95.
Dia mengkomparasi paradigma studi keagamaan di Aceh dengan akar genealogi
keilmuan Hamzah Fansûrî dan Hegel. Turunan kajian Hamzah Fansûrî dilakukan
oleh Syed Muhammad Naquib Al-Attas yang memengaruhi keseluruhan pemikiran
profesor dari Malaysia itu. Sementara Turunan kajian Hegel dilakukan oleh Snouck
Hurgronje96 dan beberapa orientalis lainnya. Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad
dalam penelitiannya itu menawarkan ajaran-ajaran Hamzah Fansûrî dapat dijadikan
paradigma ideal dalam melakukan penelitian dan kajian tentang Aceh.
Terdapat juga beberapa penelitian tentang pemikiran Hamzah Fansûrî yang
dipublikasikan dalam bentuk jurnal97. Akan tetapi, umumnya penelitian dalam bentuk
jurnal bertujuan menjadikan nilai-nilai pemikiran Hamzah Fansûrî sebagai alternatif,
solusi, dan pembelaan atas pemikirannya.
Ismail Fahmi Arrauf Nasution menulis tentang humanisasi pendidikan melalui
antropologi transendental Hamzah Fansûrî98. Dalam penelitiannya itu, dia berfokus
mengkaji syarah ‘Ruba’i’ Hamzah Fansûrî yang ditulis Shams al-Dîn al-Sumatranî
dan mengambil nilai-nilai humanisme sebagai fondasi paradigma pendidikan
humanis. Ismail Fahmi Arrauf Nasution juga membahas semangat ajaran Wahdah al-
Wujûd Hamzah Fansûrî yang terkandung dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur’an99.
Pada kesempatan lainnya, Ismail Fahmi Arrauf Nasution juga meneliti tentang
hilangnya ajaran Wujudiah Hamzah Fansûrî oleh ajaran teologis ‘Abd al-Ra’uf al-
Sinkilî100. Menurutnya, meskipun ‘Abd al-Ra’uf al-Sinkilî tidak melakukan serangan
yang keras terhadap Wujudiah sebagaimana dilakukan Nûr al-Dîn al-Ranîrî, tetapi
pengaruh ‘Abd al-Ra’uf al-Sinkilî yang mendalam, menyeluruh, dan dalam durasi
yang lama sebagai Mufti Kesultanan Aceh Darussalam membuat ajaran Wujudiah
benar-benar hilang di Aceh.
Di samping itu, Syaifan Nur pernah melakukan penelitian tentang
pembelaannya terhadap ajaran Hamzah Fansûrî dari kritik yang dilakukan oleh Nûr
al-Dîn al-Ranîrî101. Dalam kajian tersebut, Syaifan Nur menunjukkan kelemahan-
kelemahan argumentasi yang dibangun oleh Nûr al-Dîn al-Ranîrî dalam menyerang
gagasan-gagasan Hamzah Fansûrî.
95 Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Kontribusi Charles Taylor, Syed Muhammad
Naquib Al-Attas, and Henry Corbin Dalam Studi Metafisika & Meta Teori Terhadap Islam
Nusantara Di Indonesia…, 40. 96 Snouck Hurgronje, Orang Aceh (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 39. 97 Bagus Laksana, “The Mystery Of The Human Person : Mystical Anthropology In
Hamzah Fansuri’s Shair,” Kanz Philosophia : A Journal for Islamic Philosophy and
Mysticism 6, no. 1 (2016): 33–51; Yani, “Analisis Tematik Terhadap Syair Burung Pingai
Karya Hamzah Fansuri”, 20 ; Riddell, “Breaking the Hamzah Fansuri Barrier, 125-140” 98 Nasution, “Humanisasi Pendidikan Islam Melalui Antropologi Transendental
Hamzah Fansûrî.”, 235. 99 Ismail Fahmi Arrauf Nasution, “Waḥdat Al-Wujûd Dalam Alquran,” Mutawattir 6,
no. 2 (2016): 258–283. 100 Ismail Fahmi Arrauf Nasution, “Termination of Wahdatul Wujud In Islamic
Civilization In Aceh: Critical Analysis of Ithaf Ad-Dhaki, The Works of Ibrahim Kurani.”,
401. 101 Syaifan Nur, “Kritik Terhadap Pemikiran Tasawuf Al-Raniri.”, 137
33
Sementara itu, penelitian tentang ajaran Mullâ Sadrâ juga telah dilakukan
beberapa peneliti. Di antaranya, Hasan Bakti Nasution melakukan penelitian tentang
model sintesis pemikiran Islam oleh Mullâ Sadrâ. Penelitian itu merupakan disertasi
doktoral di IAIN Jakarta pada 2001 di bawah bimbingan Mulyadhi Kartanegara dan
Jalaluddin Rakhmat102. Penelitian lainnya tentang pemikiran Mullâ Sadrâ dilakukan
oleh Syaifan Nur di IAIN Sunan Kalijaga pada 2002. Disertasi tersebut fokus pada
kajian filsafat Wujud yang digagas Mullâ Sadrâ103.
Sementara itu, kajian perbandingan filsafat telah banyak dilakukan.
Muhammad Iqbal telah melakukan kajian metafisika Persia dalam disertasinya.
Penelitian ini fokus pada analisis berbagai varian kajian metafisika di dunia Persia,
seperti Aristotelianisme dan Neoplatonisme, Idealisme dan Rasionalisme, serta
mengkaji tentang respons para filosof atas perkembangan teologi dan tasawuf. Di
antaranya adalah Toshihiko Izutsu telah meneliti perbandingan pemikiran filsafat
mistisme Ibn ‘Arabi dan Taoisme104. M. Amin Abdullah telah meneliti tentang filsafat
etika antara Abû Hamid al-Ghazalî dan Immanuel Kant105. Arpaslan Achicgenk telah
meneliti tentang perbandingan ontologi antara Mullâ Sadrâ dan Martin Heideggar106.
Dari kajian-kajian di atas, belum ditemukan kajian perbandingan atas
pemikiran Hamzah Fansûrî dan filsafat Mullâ Sadrâ. Terdapat perbedaan dan
persamaan antara dua pemikir ini. Di antara perbedaan keduanya tentunya adalah
mereka berasal dari latar belakang budaya dan tradisi ilmu pengetahuan yang
berbeda. Di antara persamaan pentingnya adalah mereka sama-sama mengakui
kemendasaran wujûd. Persamaan penting ini dapat membingkai pemikiran Hamzah
Fansûrî dan Mullâ Sadrâ dalam sebuah kajian komparatif.
Objek kajian dalam penelitian ini adalah pemikiran ontologi Hamzah Fansûrî
dan Mullâ Sadrâ serta perbandingan antara kesamaan dan perbedaan keduanya. Jenis
penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menganalisis
dan mengonstruksi pemikiran Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ serta perbandingan
antara kesamaan dan perbedaan keduanya berdasarkan sumber kepustakaan. Metode
penelitian ini adalah deskriptif-analitis-komparatif. Deskriptif adalah berusaha
mendeskripsikan latar belakang dan pembangunan pemikiran masing-masing antara
Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ. Analitis adalah berusaha mengkaji pemikiran
Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ untuk menghasilkan narasi atas keunikan tiap-tiap
tokoh. Selanjutnya adalah komparatif, yakni berusaha menemukan persamaan dan
perbedaan dari pemikiran Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ. Hasil dari kajian
perbandingan ini juga akan menunjukkan dampak dari tiap-tiap ajaran sehingga akan
102 Hasan Bakti Nasution, “Hikmah Muta’alliyah: Analisa Terhadap Proses Sintesa
Filosofis Mulla Sadra”, 15. 103 Syaifan Nur, Syaifan, Filsafat Hikmah Mulla Sadra (Yogyakarta: Rausyan Fikr,
2012), 22. 104 Toshihiko Izutsu, Sufism and Taoism: A Comparative Study of Key Philosophical
Concepts (Berkeley, Los Ageles London: University of California Press, 1983), 3. 105 M. Amin Abdullah, Antara Al-Ghazali Dan Kant: Filsafat Etika Islam (Bandung:
Mizan, 2002), 35. 106 Alparslan Açıkgenç, Being and Existence in Ṣadrā and Heidegger, 36.
34
dideskripsikan perbandingan kelanjutan dari ajaran Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ
di negerinya masing-masing.
Data primer penelitian ini adalah kitab naskah Asrâr yang merupakan karya
filosofis Hamzah Fansûrî yang terlampir di dalam karya Syed Muhammad Naquib
Al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansûrî107 dan karya-karya penting tentang
kajian atas pemikiran Hamzah Fansûrî, seperti karya Naquib Al-Attas dan Tasawuf
yang Tertindas karya Abdul Hadi WM. Sementara untuk analisis pemikiran Mullâ
Sadrâ peneliti berusaha merujuk argumentasi penting pemikirannya dari karya
penting Mullâ Sadrâ, seperti Asfar dan al-Masya’ir serta karya-karya tentang Mullâ
Sadrâ.
Antara Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ masing-masing memiliki sistem dan
keunikan dalam membangun pemikirannya. Perbedaan ini tidak lepas dari dua
konteks budaya yang berbeda. Penelitian ini dimulai dengan memfokuskan analisis
pada pokok-pokok pikiran tiap-tiap tokoh dan gagasan-gagasan masing-masing.
Dimulai dengan menganalisis latar belakang munculnya pemikiran Hamzah Fansûrî
dan Mullâ Sadrâ. Selanjutnya, menganalisis dasar-dasar pemikiran dan gagasan
Hamzah Fansûrî dalam bentuk analogi sebagai bagian keunikan pemikirannya. Lalu,
menganalisis pokok pemikiran dan konsep-konsep penting dalam pemikiran Mullâ
Sadrâ. Terakhir, menganalisis persamaan dan perbedaan pemikiran Hamzah Fansûrî
dan Mullâ Sadrâ.
Penelitian ini merupakan kajian perbandingan ontologi. Meskipun demikian,
aspek-aspek yang berkaitan dengan ontologi dari ajaran Hamzah Fansûrî dan Mullâ
Sadrâ juga tidak diabaikan. Penelitian komparatif bukan bertujuan mencari pemikiran
mana yang lebih unggul daripada pemikiran lainnya. Penelitian komparatif bertujuan
menemukan keunikan dari tiap-tiap pemikiran dan berusaha mencari perbedaan dan
persamaan keduanya108. Penelitian ini berusaha menemukan keunikan masing-
masing antara Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ persamaan dan perbedaan pemikiran
Hamzah Fansûrî dan Mullâ untuk menemukan persamaan dan perbedaan pemikiran
keduanya.
Para peneliti kajian perbandingan filsafat, seperti M. Amin Abdullah,
Toshihiko Izutsu, dan Arpaslan Achicgenk sepakat bahwa kajian perbandingan
filsafat adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari tiap-tiap ajaran.
Namun, mereka menggunakan pendekatan yang berbeda-beda dalam melakukan
kajian perbandingan.
Dalam penelitian ini, metode untuk menemukan persamaan dan perbedaan
ajaran ontologi antara Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ menggunakan sistem relasi
107 Karya Syed Muhammad Naquib Al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansûrî,
memuat tiga prosa Hamzah Fansûrî secara lengkap yang telah ditransliterasi. Untuk
memudahkan pembedaan rujukan, maka setiapprosa Hamzah Fansûrî dipisahkan
pengutipannya untuk memudahkan pengenalan rujukan antar prosa-prosa itu dan pandangan
Syed Muhammad Naquib Al-Attas sendiri. Dalam buku tersebut, transliterasi Asrâr terletak
pada halaman 233 hingga 296, Syarâb pada halaman 297 hingga 328, dan al-Muntahî pada
halaman 329 hingga 353. 108 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Yogyakarta: Paradigma,
2005), 291.
35
dalam ilmu logika. Abdul Hadi Fadli mengatakan terdapat empat relasi, yakni
ekuivalen, relasi umum dan khusus secara mutlak, dan relasi umum dan khusus dari
satu sisi109. Sementara relasi nonekuivalen dijadikan kategori dimensi perbedaan.
Hasil kajian perbandingan atas setiap unit persamaan dan perbedaan antara ajaran
Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ akan disimpulkan ke dalam salah satu dari empat
relasi ini.
Gambar. 1 Empat jenis relasi
ekuivalen Umum-
khusus mutlak
nonekuivalen Umum-
khusus satu
sisi
109 Abdul Hadi Fadli, Logika Praktis , 39.
36
BAB II
TEORI WUJÛD DALAM FILSAFAT DAN WUJUDIAH
Bagian ini membahas tentang konsep wujûd, perkembangan diskursusnya, dan
kata yang semakna dengannya serta konsep-konsep berkaitan dengan wujûd dalam
tradisi filsafat dan tasawuf filosofis atau disebut dengan Wujudiah. Kata wujûd
sendiri memiliki padanan makna yang sangat jauh hingga filsafat Yunani. Plato
memulai diskursus tentang wujûd yang diistilahkan dengan ontos yang eksis pada
realitas materi dan alam ide. Menurutnya, ontos pada realitas ide adalah lebih utama
dibandingkan ada realitas ide. Selanjutnya, Aristoteles membahas tentang wujûd
utama sebagai segala sebab bagi alam semesta yang diistilahkan dengan Prima
Causa. Selanjutnya, Plotinus membagi wujûd kepada empat tingkatan, yakni
eksistensi pertama, nous, jiwa alam (first soul), dan eksistensi alam.
Kemudian, diskursus tentang wujûd diambil alih oleh para filosof muslim yang
secara umum terbagi menjadi al-Hikmah al-Masya’iyyah yang diwakili oleh al-
Kindî, al-Farabî, Ibn Sîna, dan Ibn Rusyd. Kemudian, aliran al-Hikmah al-
Isyraqiyyah yang didirikan oleh Syihab al-Dîn al-Suhrawardî dan diikuti oleh Qutb
al-Dîn Shirazî. Selanjutnya, al-Hikmah al-Muta’alliyah yang didirikan Mullâ Sadrâ
dan pengikutnya, seperti Mullâ Hâdî Sabzawârî, Sayyid Hussîn Thabattâbâ'i, Sayyid
Haydar Amûlî, Muhammad Taqî Misbah Yazdî, dan lainnya. Tiap-tiap aliran tersebut
memiliki pemahaman yang unik tentang wujûd. Pemahaman-pemahaman itu dibahas
dalam bab ini.
Demikian juga aliran tasawuf filosofis memiliki pembahasan yang mendalam
tentang wujûd. Diskursus wujûd dalam Wujudiah telah dimulai oleh sufi generasi
awal sejak Rabi’ah al-Adawiyah, Sufyân al-Tsaurî, Dhu’nûn al-Misrî, dan lainnya.
Kajian tersebut kemudian dilanjutkan oleh sufi generasi pertengahan, seperti Abû
Yazid al-Bistamî, Junayd al-Baghdadî, Abû Mansûr al-Hallaj, ‘Ain al-Qudat al-
Hamadanî, dan lainnya. Kemudian, konsep wujûd beserta diskursus berkaitan
dengannya disempurnakan oleh Ibn ‘Arabi dan dilanjutkan oleh para pengikutnya,
seperti ‘Abd al-Karîm al-Jîlî, Fadhl Allah al-Burhânpûrî, Hamzah Fansûrî, dan
lainnya.
A. Teori Wujûd dalam Filsafat Islam
Ibn Sînâ sebagai representasi ideal al-Hikmah al-Masya’iyyah membahas
tentang wujûd pada bagian awal karyanya110. Sistem ini berbalikan dengan
penyusunan kodifikasi karya Aristoteles setelah dia meninggal. Karya-karya
Aristoteles disusun dengan menempatkan pembahasan tentang ketuhanan (atau
ilahiah, atau wujûd sebagaimana adanya, being qua being) pada bagian terakhir
dengan diberi judul “Metafisika”. Judul tersebut lahir karena susunan karya
Aristoteles tentang being qua being diletakkan setelah (meta) pembahasan tentang
ilmu kealaman. Maka dari itu, terjadi kesalahan terminologi. Seharusnya disebut pro-
110 Shams Inati, “Ibn Sina,” in History of Islamic Philosophy Vol. I, ed. Seyyed Hossein
Nasr dan Oliver Leaman (London & New York: Routledge, 1996), 233.
37
fisika111. Akan tetapi, maksud akuratnya adalah pembahasannya tentang wujûd yang
mendahului sebagai mawjûd. Pembahasan tentang wujûd sebagaimana wujûd (being
qua being) disebut sebagai ontologi, yakni ilmu tentang wujûd (ontos: ada, logos:
ilmu). Kata wujûd sendiri berasal dari kata wujîda yang secara literal berarti
‘ditemukan’. Wujud berarti “keberadaan” yang diperbandingkan dengan kata
mâhiyâh, yakni ke atau “ke-apa-an” atau “ke-sesuatu-an”. Lawan dari wujûd adalah
‘adam, yakni ketiadaan.
Kajian wujûd dalam terminologi umum pemikiran Islam (kâlâm, al-hikmah,
dan ‘irfan) dapat disebut sebagai pembahasan tentang al-Ilahiyah. Terminologi al-
Ilahiyah dapat diterima oleh filsafat Islam (al-Ilahiyah), dan juga teologi Islam
(kâlâm). Dalam hal ini, tasawuf juga dapat menerima terminologi al-Ilahiyah
meskipun aliran ini memiliki istilah khusus tentang ilahiah dalam diskursusnya, yakni
Haqq (Al-Haqq atau Haqq Ta’ala). Mengikuti makna sebenarnya dari metafisika
(yang mencakup ontologi, ilmu tentang “ada”) maka sebenarnya pembahasan tentang
fisika tidak boleh dipisahkan dengan metafisika. Pemisahan fisika dan metafisika
terjadi akibat kesalahan pemahaman penggunaan istilah ontologi sebagai metafisika.
Oleh sebab itu, para filosof muslim (hukamâ) sekalipun memenuhi kriteria sebagai
filosof, yakni menjadikan akurasi proposisi dan penalaran sebagai fondasi, tetap saja
orientasi mereka adalah al-Ilahiyah atau Wujûd Yang Absolut112.
Orientasi kajian wujûd ilahiah ini tidak hanya disadari oleh Syihab al-Dîn al-
Suhrawardî maupun Mullâ Sadrâ yang menegaskan bahwa filosof yang benar adalah
yang memiliki pengalaman spiritual sekaligus ketepatan dalam berfilsafat113.
Orientasi ini telah menjadi estimasi al-Fârâbî yang ditandai dengan kekecewaannya
pada filsafat Aristoteles yang sangat sedikit berbicara tentang wujûd keilahian
sehingga dia meminjam konsep emanasi Neo-Platonis dalam filsafatnya114. Begitu al-
Fârâbî, apalagi para mutakallimîn, tentunya hanya menggunakan kaidah berpikir
filsafat untuk mendukung pandangan tentang wahyu. Tidak dapat dimungkiri, tidak
hanya al-Asy’ariyah dan Matûridiyah, bahkan Mu'tazilah sekalipun melakukan hal
yang sama. Kecenderungan keagamaan yang sangat kental bagi para pemikir muslim
mendesak filsuf seperti al-Kindî, Al-Fârâbî, dan Ibn Sînâ bekerja keras
mengintegrasikan filsafat untuk dekat dengan agama, yang bagi al-Fârâbî dan Ibn
Sînâ ditandai dengan akomodasi Neoplatonisme ke dalam studi metafisika mereka.
Akomodasi inilah yang melahirkan sistem emanasi dalam mazhab Peripatetik Islam
(al-Hikmah al-Masya’iyyah).
Dari al-Fârâbî, Ibn Sînâ memandang pentingnya studi wujûd dalam filsafat.
Sesuatu yang dalam filsafat Yunani maupun Barat tidak terlalu penting, yakni
metafisika, oleh filosof muslim (hukâma), seperti Ibn Sînâ misalnya, menawarkan
111 Murtaha Muthahhari, Filsafat Hikmah: Pengantar Pemikiran Shadra,
)Bandung: Mizan, 2002), 51–52. 112 Ismail Fahmi Arrauf Nasution, “Mencerna Akar Filsafat Dalam Islam,” Ulumuna
17, no. 1 (November 8, 2017): 1–18, http://ulumuna.or.id/index.php/ujis/article/view/236. 113 Toshihiko Izutsu, Struktur Metafisika Sabzawari (Bandung: Pustaka, 2003), 16. 114 Mulyadhi Kartanegara, Gerbang Kearifan: Sebuah Pengantar Filsafat Islam
(Jakarta: Lentera Hati, 2006), 37.
38
“metafisika” menjadi “pro-fisika” karena dia, sebagai satu petanda khas filosof
muslim, melihat signifikansi diskursus wujûd yang bersifat Ilahiyah. Al-Hikmah al-
Masya’iyyah yang dikenal sangat rasional sekalipun ternyata sangat konsen pada
diskursus wujûd. Apalagi filsafat Illuminasionisme Islam (al-Hikmah al-Isyraqiyah)
yang sudah bersifat sangat Ilahiyah. Bahkan, Syihab al-Dîn al-Suhrawardî mengkritik
kaidah-kaidah epistemologi al-Hikmah al-Masya’iyyah secara sangat keras. Namun
sebenarnya, Ibn Sînâ sendiri, pada periode akhir hidupnya menawarkan epistemologi
yang mirip dengan epistemologi al-Hikmah al-Masya’iyyah115. Ibn Sînâ menulis al-
Hikmah al-Masyriqiyyah. Oleh sebab itu, Syihab al-Dîn al-Suhrawardî, bila
direlasikan secara periodik dengan Ibn Sînâ, adalah kelanjutan dari Ibn Sînâ sendiri.
Begitu al-Hikmah al-Masya’iyyah dan al-Hikmah Isyraqiyyah, apalagi al-Hikmah al-
Muta'aalliyah. Mazhab filsafat yang dinisbahkan kepada Mullâ Sadrâ ini bahkan
menjadi sangat sulit dibedakan dengan Wujudiah.
Dari alasan-alasan di atas, sudah jelas bahwa filsafat Islam bukanlah sebuah
aliran pemikiran yang sama dengan filsafat Yunani. Terdapat sebuah pembentukan
identitas baru yang membedakannya dengan filsafat Yunani, baik itu Aristotelian
maupun Neo-Platonis. Hal yang sangat jelas dari perbedaan filsafat Yunani dengan
filsafat Islam adalah diskursus ontologi menjadi lebih tajam dalam pemahaman wujûd
yang dimulai oleh al-Fârâbî, dilanjutkan oleh Ibn Sînâ, Syihab al-Dîn al-Suhrawardî,
dan dilakukan usaha sintesis oleh Mullâ Sadrâ.
Tidak dapat dimungkiri, porsi kajian Wujûd Ilahiyah yang menjadi inti dan
mendapatkan porsi yang lebih dalam filsafat Islam bukan hanya ingin mendekatkan
filsafat kepada dunia muslim dan meminimalkan resistensi otoritas agama, melainkan
memang menjadi karakteristik dan kecenderungan religius para filosofnya. Sebab
itulah, hukâmâ menyebutkan filsafat sebagai hikmah. Seyyed Hossein Nasr, sarjana
filsafat yang memulai tradisi filsafat dengan belajar kepada para filosof kontemporer
mengatakan bahwa filsafat Islam itu adalah pembahasan tentang wujûd sebagaimana
adanya (asyya’ al-mawjūdah bî mâ hiya mawjûdah). Filsafat adalah pengetahuan
tentang wujûd Ilahiyah dan insaniyah. Filsafat adalah prasyarat bagi hikmah.
Dengan kecenderungan kajian Wujûd Ilahiyah dalam filsafat Islam maka
dengan jelas tidak hanya membedakannya dari filsafat Yunani, tetapi juga
membentuk demarkasi dengan filsafat Barat Modern116. Filsafat Barat Modern yang
dapat ditandai mulai Rene Descartes dan David Hume, lebih berfokus pada
kecenderungan epistemologis dan menghilangkan dimensi wujûd yang menjadi ciri
khas filsafat Islam. Sebab itulah, Nasr117 menawarkan istilah hikmah bagi filsafat
Islam dan falasifah kepada filsafat Barat. Filsafat Barat Modern yang
berkecenderungan sebatas pada kajian penalaran dengan mudah dimaknai para
115 Hossein Ziai, “Shihab Al-Din Suhrawardi: Founder of the Illuminationist,” in
History of Islamic Philosophy Vol. I, ed. Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman (London
& New York: Routledge, 1996), 436. 116 Yoyo Hambali, “Eksistensi Manusia Dalam Filsafat Pendidikan : Studi Komparatif
Filsafat Barat Dan Filsafat Islam,” Jurnal FAI: Turats 7, no. 1 (2011): 42–56. 117 Seyyed Hossein Nasr, dalam History of Islamic Philosophy Vol. I, Diedit oleh
Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman, 21. (London & New York: Routledge, 1996), 33.
39
sarjana sebagai bagian dari ilmu-ilmu sosial118. Dalam perspektif filsafat Barat
Modern, tentu saja ini tidak sepenuhnya keliru meskipun tidak sepenuhnya benar.
Akan tetapi, ketika muncul generalisasi atas filsafat yang memasukkan filsafat Islam
di dalamnya, itu menjadi galat. Pandangan seperti ini menjadikan makna filsafat
Islam menjadi meleset119.
Filosof muslim yang serius memaknai filsafat Islam sebagai hikmah adalah
Syihab al-Dîn al-Suhrawardî120. Akan tetapi, kecenderungan Syihab al-Dîn al-
Suhrawardî bukan hanya karena menemukan diskursus filsafat Islam memiliki
konsentrasi Ilahiah yang kuat, melainkan juga karena alasan historis. Syihab al-Dîn
al-Suhrawardî mengatakan, filsafat menjadi kering dari dimensi Ilahiah dimulai dari
Aristoteles. Sebelumnya, filsafat memiliki fokus diskursus Ilahiyah yang tinggi
hingga Plato. Berkat Syihab al-Dîn al-Suhrawardî, pemikir seperti Mullâ Sadrâ
menjadikan filsafat menjadi makin berkecenderungan Ilahiyah. Dipengaruhi Syihab
al-Dîn al-Suhrawardî dan memberikan sedikit pengembangan, Mullâ Sadrâ
mendefinisikan filsafat sebagai upaya penyempurnaan jiwa manusia atas
kemampuannya melalui eksistensi berdasarkan demonstrasi, bukan asumsi atau
opini. Maksud dari definisi Mullâ Sadrâ tentang filsafat setidaknya dapat
mempertajam makna filsafat dan alasan kenapa istilah untuk filsafat Islam disebut al-
hikmah.
Dalam sistem filsafatnya, Mullâ Sadrâ menjelaskan bahwa manusia
menempuh empat perjalanan dalam hidupnya. Empat perjalanan ini dipahami
seorang filosof dan merumuskan penjelasan dalam perjalanan ini secara konseptual.
Konseptualisasi filsafat, sebagaimana dalam definisi Mullâ Sadrâ, adalah konsep-
konsep yang dibangun berdasarkan prinsip epistemologi filsafat, yakni melalui
proposisi-proposisi yang solid dan sesuai dengan kaidah berpikir benar sebagaimana
dijelaskan melalui ilmu logika atau mantiq121. Proposisi-proposisi yang dibangun
dalam terminologi filsafat Islam (sehingga layak disebut hikmah) adalah sesuai
dengan pengalaman mistiknya hingga seorang filosof (sehingga layak disebut hakim).
Sebab itulah, Mullâ Sadrâ sangat setuju dengan kualifikasi seorang filsuf yang
dirumuskan Syihab al-Dîn al-Suhrawardî, yakni adalah dia yang memperoleh
pengalaman langsung (hudhûrî) dan mampu menyampaikan pengalaman itu dalam
kaidah filsafat122. Dengan menjadikan pendasaran pada konseptualisasi pengalaman
intuisi pada demonstrasi maka sedikit menunjukkan demarkasi ajaran Mullâ Sadrâ
dengan tasawuf filosofis. Dalam tasawuf filosofis, tidak diperlukan demonstrasi
untuk menjadi landasan. Landasan mereka untuk mengenal hakikat wujûd adalah
kasyaf hudhûrî. Namun, Mullâ Sadrâ sendiri sangat mementingkan kasyaf hudhûrî.
118 Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman, “Memahami Sejarah Intelektual Isaiah Berlin
(1909-1997),” ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin (2016), 279. 119 Nasution, “Mencerna Akar Filsafat Dalam Islam.”…, 1-18 120 A. Khudori Soleh, “Filsafat Isyraqi Suhrawardi,” ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu
Ushuluddin 12, no. 1 (January 22, 2011): 1, http://ejournal.uin-
suka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/view/121-01. 121 Abdul Hadi Fadli, Logika Praktis, (Jakarta: Sadra Press, 2016), 4–12. 122 Cipta Bakti Gama, Filsafat Jiwa: Dialektika Filsafat Islam, Dan Filsafat Barat
Kontemporer (Malang: Pustaka Sophia, 2018), 118–119.
40
Mullâ Sadrâ membangun konsep filsafat yang menyatakan bahwa segala
fakultas manusia, dalam semua tingkatannya, baik itu pengalaman indrawi, analisis
rasional, maupun pengalaman kasyaf adalah kehadiran jiwa dalam tingkatan yang
berbeda. Mullâ Sadrâ menegaskan bahwa persepsi indrawi itu adalah kehadiran jiwa
sama, seperti analisis rasional dan kasyaf. Pandangan ini berbeda dengan beberapa
aliran filsafat, termasuk al-Hikmah al-Masyâ'iyyah yang masih memperlakukan jiwa
dan jasad sebagai dualitas123.
Tokoh pertama yang berkecenderungan untuk membangun kajian wujûd dalam
filsafat Islam adalah al-Kindî124. Sekitar tiga ratus judul karya telah ditulis al-Kindî125.
Dia menulis tema keilmuan secara luas dari metafisika, matematika, hingga ilmu-
ilmu kealaman. Akan tetapi, yang telah berhasil diteliti dan diedit hanya sekitar
sepuluh persen. Sebagian besar karyanya hilang. Bisa jadi diabaikan karena bahasa
al-Kindî buruk akibat kurang terfasilitasinya filsafat kaidah-kaidah ke dalam bahasa
Arab. Memang Al-Kindî filsuf Islam pertama yang mencari padanan-padanan kaidah
filsafat ke dalam lingkungan Bahasa Arab. Boleh jadi karya-karya al-Kindî turut
dibuang ke sungai Tigris pada penaklukan Mongol126. Mungkin munculnya al-Fârâbî
yang juga memiliki karya ensiklopedis dapat mengobati kekecewaan akan hilangnya
sebagian besar karya al-Kindî. Jelas bahwa pada masa al-Kindî, pembelajaran filsafat
memang sudah sangat berkembang di Baghdad127. Penerjemahan filsafat Yunani
sudah sangat gencar jauh sebelum al-Kindî. Bahkan, Felix Klein-Franke mengeklaim
al-Farabî tidak dapat berbahasa Yunani maupun Suryani yang menjadi bahasa asli
penulisan filsafat Yunani. Ibn Nai'iman, Eusthatius, dan Ibn al-Bithriq adalah
sebagian dari penerjemah karya Yunani dan Suryani yang sangat membantu. Ahmed
Fuad Ehnawy mengatakan, tugas utama al-Kindî adalah mengharmoniskan agama
dan filsafat128. Tugas ini dikerjakan al-Kindî dengan usaha yang kuat, mengingat
tingginya tingkat resistansi para teolog dan ahli fikih. Al-Kindî dapat dilihat sebagai
seorang filsuf yang heroik. Dia sanggup mengatasi tekanan-tekanan itu129.
Tidak dapat dimungkiri, perlindungan penguasa pada masa itu membuat usaha
al-Kindî menjadi lebih mudah. Akan tetapi, dalam posisi tidak mampu berbahasa
Yunani dan Suryani maka pekerjaan al-Kindî dapat dikatakan sebagai usaha yang
benar-benar heroik130. Ketika mengulas karya-karya Neo-Platonis, al-Kindî tidak
terlalu mendapatkan resistansi. Akan tetapi, dalam mengulas karya-karya Aristoteles,
123 Cipta Bakti Gama, Filsafat Jiwa…, 118. 124 Kiki Kennedy-Day, “Al-Kindi,” in Books of Definition in Islamic Philosophy
(Abingdon, UK: Taylor & Francis, 2010), 19–31,
https://www.taylorfrancis.com/books/9780203221372. 125 Felix Klein-Franke, “Al-Kindi,” in History of Islamic Philosophy Vol. I, ed. Seyyed
Hossein Nasr and Oliver Leaman (London & New York: Routledge, 1996), 168. 126 Michal Biran dan Thomas T. Allsen, “Culture and Conquest in Mongol Eurasia,”
Journal of the American Oriental Society (2003), 446. 127 Ahmed Fuad Ehnawy, “Al-Kindi,” dalam A History of Muslim Philosophy Vol. I
(New Delhi: Low Price Publications, 1995), 427. 128 Ahmed Fuad Ehnawy, “Al-Kindi …, 425. 129 Jackson, What Is Islamic Philosophy?..., 33–34. 130 Sebagian sarjana meyakini al-Kindî dapat berbahasa Arab dan bahasa Suryani,
sebagian lainnya meyakini dia tidak menguasainya. Lihat, Klein-Franke, “Al-Kindi,” 167.
41
resistansi menjadi tinggi. Masalahnya karena karya-karya Aristoteles terlalu kering
dari nuansa kajian Wujûd Ilahiyah. Al-Kindî menjadi sangat berbahagia ketika
menemukan sebuah risalah yang memberi porsi yang tinggi terhadap kajian Wujûd
Ilahiyah dan ternyata itu baru diketahui terkemudian setelah Mullâ Sadrâ bahwa
risalah itu bukan karya Aristoteles, melainkan kajian metafisika Plotinus yang ditulis
murid Plotinus, Porphyry131. Karya berjudul Enneads itu telah mengecoh para filosof
muslim dari al-Kindî hingga Mullâ Sadrâ. Al-Kindî yang terlalu bahagia dan
mengambil banyak manfaat dari Enneads kurang berhati-hati dalam melacak karya
tersebut. Dia terlalu senang dengan menganggap Aristoteles juga memiliki karya
Ilahiyah sehingga resistansi atas kajian Aristoteles menjadi berkurang132. Melalui
karya Enneads, al-Kindî merumuskan konsep Wujûd Ilahiyah perspektif filsafat
dengan mengatakan bahwa segala realitas ini adalah akibat yang berantai dari sebab-
sebab hingga kembali kepada sebab yang bukan akibat dari sebab lain133. Sebab itu,
disebut Prima Causa. Dengan keterangan ini, al-Kindî dapat berbahagia karena dapat
merelasikan terminologi Prima Causa dengan “Yang Esa” sebagai sebab dari segala
sebab134.
Al-Kindî datang meletakkan dasar filsafat dalam Islam135. Sebelumnya, filsafat
memang telah dipelajari dalam dunia Islam, tetapi belum ada yang menyusun filsafat
sebagai sebuah sistem yang berdasarkan epistemologi khas filsafat. Sebelum al-
Kindî, hanya keilmuan-keilmuan lain, seperti matematika (filsafat menengah
menurut al-Fârâbî nantinya), logika (yang diambil fuqaha dan mutakallimîn) untuk
argumentasi pembelaan wahyu dan penyusunan hukum-hukum. Ilmu-ilmu kealaman
atau filsafat terakhir menurut al-Fârâbî, juga dikembangkan dalam dunia Islam.
Kajian wujûd tidak terlalu dilirik. Selain literaturnya yang minim, juga ilmu tersebut
dianggap tidak layak diajarkan karena di dalam wahyu, kajian wujûd sudah sangat
memadai. Di samping itu, metafisika Yunani dihindari karena dianggap bisa
menentang wahyu. Akan tetapi, al-Kindî mencoba memulai kajian wujûd yang mana
keputusan ini sangat dipengaruhi Enneads.
Al-Kindî membagi filsafat menjadi dua bagian, yakni filsafat tinggi dan
filsafat bawah. Filsafat tinggi mencakup Wujûd (Prima Causa), jiwa, dan akal.
Sementara filsafat bawah meliputi kajian ilmu-ilmu fisika. Filsafat bawah yang
dibahas al-Kindî juga meliputi kajian tentang jasad, ciptaan, materi, dan bentuk.
Menurut al-Kindî, objek kajian wujûd alam bawah itu diciptakan dari ketiadaan dalam
dimensi waktu. Pandangan ini tentunya tidak membuat mutakallimîn resah karena
teologi juga mengakui wujûd alam diciptakan dari ketiadaan. Dalam kajiannya
tentang wujûd, al-Kindî mengatakan bahwa penciptaan terjadi melalui emanasi.
Prima Causa sebagai wujûd sebab tertinggi terus-menerus memancarkan diri
131 Jonathan Scott Lee, dan Dominic J. O’Meara, “Plotinus: An Introduction to the
Enneads,” The Classical World (1996), 229. 132 Kartanegara, Gerbang Kearifan: Sebuah Pengantar Filsafat Islam…, 36. 133 El-Hanawy, “Al-Kindi,” dalam A History of Muslim Philosophy Vol. I, ed. M.M.
Sharif, III. (New Delhi: Low Price Publications, 1995), 424. 134 Klein-Franke, “Al-Kindi”…, 174. 135 Kennedy-Day, “Al-Kindi”…, 26.
42
sehingga terjadilah wujûd alam dalam berbagai tingkatannya136. Pandangan yang
sudah sarat kajian Wujûd Ilahiyah ini tetap menimbulkan resistansi dari sebagian
mutakallimîn karena al-Kindî dianggap memberikan porsi yang tinggi terhadap akal.
Malaikat Jibril disebut sebagai Akal Aktif. Sementara kewahyuan dianggap sebagai
capaian jiwa. Namun sebenarnya, “akal” digunakan al-Kindî sebagai pengistilahan
khas filsafat bagi wujûd. Sementara al-Kindî sendiri mengakui, penalaran manusia
tidak akan dapat mencapai pengetahuan pada Wujûd Mutlak. Menurut al-Kindî,
penalaran hanya mampu memahami negasi terhadap Wujûd Mutlak137.
Klein-Frake138 menjelaskan bahwa al-Kindî, sebagai filosof pertama dalam
dunia Islam, tidak sepakat dengan absolutisitas wujûd materi sebagaimana diterima
dalam doktrin atomisme kâlâm139. Karakteristik Neoplatonik filsafat Islam yang
digagas al-Kindî dikembangkan secara radikal oleh al-Fârâbî. Dia juga merupakan
seorang filsuf varian al-Hikmah al-Masyâ'iyyah. Selain melakukan radikalisasi
emanasi wujûd ke dalam filsafat Islam, al-Fârâbî menyusun sistem logika secara
sistematis. Logika sebagai ilmu tentang kaidah berpikir benar dibedakan dengan
gramatika sebagai ilmu tentang berbahasa yang benar. Dengan penguasaan gramatika
yang baik, al-Fârâbî mampu membuat penjelasan filsafat menjadi lebih mudah
dipahami140. Karena itu, tidak mengherankan kenapa Ibn Sînâ nantinya baru dapat
memahami ajaran Aristoteles dengan baik setelah mempelajari pemikiran al-Fârâbî.
Filosof kelahiran Turki ini memang sangat memahami pemikiran Aristoteles. Hal ini
jugalah yang membuat al-Fârâbî digelari sebagai guru kedua (al-mu’allim al-tsanî)
yang mana gelar guru pertama (al-mu'allim al-ulâ) dinisbahkan kepada Aristoteles141.
Pemahaman al-Fârâbî tentang gramatologi membuat bahasa Arab menjadi makin
kompatibel untuk digunakan sebagai bahasa filsafat dan membuka banyak peluang
naturalisasi kaidah-kaidah filsafat dari bahasa Yunani dan bahasa Suryani142.
Kontribusi ini juga nantinya dimanfaatkan dengan baik oleh Ibn Sînâ dalam
menggagas filsafat wujûd-nya. Maka dari itu, manfaat kekayaan bahasa filsafat dalam
bahasa Arab juga berkontribusi terhadap aliran intelektual lain dalam dunia Islam,
seperti kajian wujûd dalam teologi dan tasawuf.
Dalam pandangan Al-Fârâbî, Tuhan adalah adalah Wujûd yang Pertama (al-
Mawjûd al-Awwal) sekaligus adalah Sebab Pertama (al-Sabab al-Awwal) bagi segala
yang mawjûd143. Dalam pemikirannya, Al-Fârâbî menjadikan kajian metafisika
wujûd dalam dunia Islam menjadi sangat Ilahiah. Sekaligus akurasi logika dan
136 Abû Isḥâq Al-Kindî, “Risâlah fî Ḥudûd Al-Asyyâ,” dalam Rasâ‛il Al-Kindiy Al-
Falsafiyyah, ed. Muḥammad ‘Abdulhâdî (Kairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabiy, t.t.), 18. 137 Abû Isḥâq Al-Kindî, “Risâlah”…, 19-20. 138 Klein-Franke, “Al-Kindi”…, 171. 139 M. Saeed Sheikh,, Islamic Philosophy (London: The Octagon Press, 1982), 131
Dalam filsafat Barat Modern, perbedaan prinsip ini yang memberikan demarkasi antara
filsafat Leibniz dan filsafat Spinoza.Miswari, Filsafat Terakhir, 258–259. 140 Fakhry, A History of Islamic Philosophy…, 107. 141 Corbin, History of Islamic Philosophy…, 160. 142 Deborah L. Black, “Al-Farabi,” dalam History of Islamic Philosophy Vol. I, ed.
Seyyed Hossein Nasr dan Oliver Leaman (London & New York: Routledge, 1996), 222. 143 Al-Fârâbî, Ara Ahl al-Madînah al Fâdhilah, (Mesir: Dâr wa Maktabah al-Hilal,
1995), 5.
43
penalaran dimulai oleh al-Fârâbî144. Akan tetapi, sebagai seorang Aristotelian, al-
Fârâbî telah menyusun sistem berpikir filsafat dengan menjadikan konsepsi
(tashawwur) dan afirmasi (tasydiq) sebagai prasyarat menghasilkan definisi dan
silogisme demonstratif. Dalam skema al-Fârâbî, pengetahuan itu harus bersifat
pasti145. Prinsip ini nantinya dijadikan landasan para filosof setelahnya untuk
menyusun hukum kepastian realitas wujûd yang menjadi rujukan pengetahuan pasti
tersebut.
Al-Fârâbî juga merupakan filsuf muslim pertama yang mengklasifikasi wujûd
dalam manifestasinya sebagai daya jiwa menjadi daya nutrisi, daya persepsi, hingga
daya inteleksi. Akan tetapi, klasifikasi ini diperjelas secara sistematis nantinya oleh
Ibn Sînâ. Daya imajinasi yang merupakan bagian dari daya jiwa dijelaskan dengan
sistematis dalam filsafat al-Fârâbî. Dalam hal ini, al-Fârâbî mengatakan bahwa daya
imajinasi berperan menyimpan gambar dari hasil persepsi indrawi. Daya ini juga
dapat membentuk modifikasi dari gambar-gambar yang tersimpan dalam imajinasi.
Misalnya, membayangkan burak dari penggabungan gambar tubuh kuda dan sayap
burung146. Kemampuan penjelasan al-Fârâbî tentang daya jiwa menghantarkannya
pada pandangan bahwa kewahyuan itu adalah kemampuan jiwa mencapai realitas
alam yang tinggi. Pandangan ini tentunya sangat bertentangan dengan ilmu kalam
dan menginspirasi sufi dan filosof setelahnya147.
Manifestasi wujûd dalam bentuk sistem intelek menjadi pembahasan penting
para filosof. Al-Fârâbî juga menyusun empat klasifikasi intelek ('alq), yakni intelek
potensial (al-'aql bi al-quwwah), intelek aktual (al-‘aql bi al-fi'’î'l), intelek perolehan
(al-'aql al-mustafad), dan intelek aktif (al-'aql al-fa'al). Intelek potensial membentuk
konsep mâhiyâh (intelligable) dari entitas ekstensi dari alam terindrai. Dari konsepsi
intelligable ini membentuk pengetahuan yang merupakan proses aktualisasi potensi.
Pengetahuan dalam skema ini menuntut perenungan hingga meraih intelek perolehan.
Dari perenungan-perenungan inilah nantinya intelek mencapai akal aktif148. Al-Fârâbî
berhasil mengarahkan konsep jiwa Aristotelian menjadi bernuansa Ilahiyah dengan
menyatakan bahwa pada capaian jiwa hingga akal aktif, di sanalah posisi kenabian149.
Black150 mengatakan bahwa sebenarnya al-Fârâbî sadar bahwa teori emanasi adalah
dari aliran Neo-Platonis. Konsep emanasi digunakan al-Fârâbî secara sengaja untuk
mengisi kekosongan diskursus Ilahiah dalam filsafat Aristotelian151. Dalam ajaran
Plotinus, Wujûd Yang Satu tidak bisa menghasilkan kemajemukan wujûd, kecuali
menghasilkan satu juga. Maka dari itu, Wujûd Yang Satu menghasilkan nous. Lalu,
144 Deborah L. Black, “Knowledge ('ilm) and Certitude (Yaqīn) dalam Al-Fārābī’s
Epistemology,” Arabic Sciences and Philosophy, 2006, 11-45. 145 Nicholas Rescher, “Al-Farabi on Logical Tradition,” Journal of the History of Ideas
(1963), 127. 146 Black, “Al-Farabi”…, 224. 147 Humaidi, Paradigma Sains Integratif Al-Farabi…, 215. 148 Black, “Knowledge ('ilm) and Certitude (Yaqīn) in Al-Fārābī’s Epistemology.”…,
20-23 149 Humaidi, Paradigma Sains Integratif Al-Farabi…, 36. 150 Black, “Al-Farabi,”…, 216. 151 Kartanegara, Gerbang Kearifan: Sebuah Pengantar Filsafat Islam,,,, 45.
44
nous menghasilkan soul, kemudian soul menghasilkan hyle. Hyle inilah yang bila
menyatu dengan bentuk dapat menghasilkan wujûd materi152.
Al-Fârâbî adalah filsuf pertama yang dengan jeli menemukan bahwa
sebenarnya Aristoteles telah menyinggung perbedaan antara esensi (mâhiyâh) dengan
eksistensi (wujûd). Perbedaan dua hal ini diambil oleh al-Farabî,
mengelaborasikannya dalam skema perbedaan wujûd dan mâhiyâh yang nantinya
menjadi bagian dari bagian filsafat Mullâ Sadrâ dan Mullâ Hadî Sabzawarî153. Wujûd
sebagai Prima Causa dalam pandangan Aristoteles sebagai pelaku aktivitas berpikir
tentang berpikir (noesis noeseos)154, oleh al-Fârâbî digambarkan sebagai Wujûd yang
berpikir tentang Diri-Nya karena pada masa itu tidak ada apa pun selain Dia sebagai
al-Awwâl. Hasil berpikir ini mewujudkan emanasi (faydh) akal atau intelek pertama.
Intelek pertama ini berpikir tentang dirinya dan sumber emanasinya, yakni al-Awwâl
hingga menghasilkan intelek kedua. Aktivitas ini terjadi hingga mencapai intelek
kesembilan155. Intelek kesembilan menghasilkan bulan (al-qamar) dan intelek
kesepuluh. Bulan menghasilkan materi. Intelek kesepuluh memberikan bentuk dan
mengaktualisasi akal manusia. Himpunan tiga entitas, yakni materi yang dihasilkan
bulan, bentuk, dan aktualitas akal dari akal kesepuluh, menghasilkan manusia dan
segala makhluk alam materi lainnya. Menghasilkan Konsep noesis noeseos inilah
yang digunakan al-Fârâbî untuk menghubungkan Aristotelian dengan Neo-Platonis
yang diisi dengan konsep kosmologi Ptolemian dan lainnya, termasuk wahyu dalam
Islam156. Al-Qur’an telah menggambarkan bahwa Tuhan menciptakan tujuh lapis
langit dan menciptakan dunia dalam tujuh masa157. Dalil-dalil ini dihubungkan
dengan konsep emanasi.
Setelah al-Kindî dan al-Fârâbî, muncul filsuf Islam selanjutnya dari kelompok
al-Hikmah al-Masyâ'iyyah yang melanjutkan pembahasan wujûd, yakni Ibn Sînâ. Dia
diberi gelar Syaikh al-Rais. Kecerdasannya dan daya ingat yang tinggi membuatnya
menguasai secara mendalam berbagai disiplin keilmuan dalam usia yang belum
remaja. Ibn Sînâ menghasilkan banyak karya, di antara yang paling terkenal adalah
al-Syifa' yang merupakan karya ensiklopedis yang membahas, secara berurutan,
yakni tentang metafisika, logika, matematika, dan fisika yang mencakup berbagai
bagian, termasuk biologi dan kedokteran158. Karya ensiklopedis penting lainnya,
152 Lee and O’Meara, “Plotinus: An Introduction to the Enneads.”,,,, 229. 153 Izutsu, Struktur Metafisika Sabzawari…, 15. 154 Reeve C. D. C., “Good and Bad in Aristotle,” in Evil in Aristotle (Cambridge
University Press, 2018), 17–31,
https://www.cambridge.org/core/product/identifier/9781316676813%23CN-bp-
1/type/book_part. 155 Majid Fakhry, “Al-Farabi and the Reconciliation of Plato and Aristotle,” Journal of
the History of Ideas (1965), 469. 156 Majid Fakhry, “Al-Farabi…, 469. 157 Muhammad Al Imron, Sodikin Sodikindan Romlah Romlah, “Meteor Dalam
Perspektif Al-Qur’an dan Sains,” Indonesian Journal of Science and Mathematics Education
(2019), 388-398. 158 Jon McGinnis, “Avicenna (Ibn Sina),” in The History of Western Philosophy of
Religion, ed. Graham Oppy (Durham: Acumen Publishing Limited, 2011), 61–72,
45
yakni al-Isyarat wa al-Tanbihat membahas tentang metafisika wujûd, logika, fisika,
dan tasawuf159.
Dalam filsafat Islam, Ibn Sînâ meneruskan tradisi diskursus wujûd yang
diwariskan al-Fârâbî. Dalam filsafat Islam, di antara pembahasan penting dalam
metafisika adalah pembahasan tentang wujûd. Istilah wujûd diambil dari istilah
bahasa Arab wujida yang berarti ‘ditemukan’. Istilah wujûd dipadankan dengan
pembahasan tentang eksistensi dalam filsafat Barat yang menggunakan istilah being.
Sementara istilah wujûd dari filsafat Islam diterjemahkan sebagai existence160.
Penjelasan tentang wujûd dibahas bersama perbedaannya dengan mâhiyâh.
Pembedaan antara wujûd dan mâhiyâh yang pertama dilakukan oleh al-Farabî atas
hasil analisisnya atas gagasan metafisika Aristoteles dilanjutkan oleh Ibn Sînâ secara
lebih mendalam. Ibn Sînâ menganalisis satu entitas (maujûdat eksisten,) dalam ranah
mental (pikiran) dan menemukan bahwa setiap entitas terbagi kepada
keberadaannnya (wujûd) dan ke-apa-annya (mâhiyâh). Dalam realitas eksternal,
suatu ekstensi memang adalah satu entitas tunggal yang tidak rangkap (antara
keberadaannya atau wujûd, dan keapaannya atau mâhiyâh). Setiap sesuatu yang dapat
menjadi jawaban atas pertanyaan “apa itu” adalah mâhiyâh161.
Ibn Sînâ mengatakan, wujûd lebih fundamental (mendasar, ashil) daripada
mâhiyâh yang hanya merupakan tambahan ('itibar) bagi wujûd. Karena setiap
ekstensi (mawjûdat) adalah satu entitas yang tidak rangkap maka konsekuensinya,
bila wujûd yang fundamental, mâhiyâh hanya sebatas konsepsi yang tidak memiliki
kenyataan. Filosof muslim setelah Ibn Sînâ seperti Syihab al-Dîn al-Suhrawardî dan
Mîr Dâmâd menentang pemikiran Ibn Sînâ dengan berpendapat bahwa mâhiyâh lebih
fundamental daripada wujûd. Alasannya itu adalah, wujûd selalu hanya menjadi
predikat bagi mâhiyâh. Misalnya, “meja itu ada”, “kuda itu ada”. Karena predikat
hanyalah kopula kausal bagi subjek, wujûd hanya bersifat majazî, tidak nyata162.
Namun ternyata, perdebatan itu muncul karena para pengkaji, baik pendukung
maupun penentang Ibn Sînâ, menganggap pernyataan Ibn Sînâ bahwa wujûd lebih
mendasar, ada pada wilayah mental. Ibn Sînâ sendiri tidak menjelaskan secara
eksplisit perbedaan ini berada di wilayah mana. Barulah setelah Nasr al-Dîn Thûsî
yang menjelaskan bahwa maksud Ibn Sînâ bahwa wujûd lebih fundamental daripada
mâhiyâh adalah pada wilayah eksternal. Sementara pada wilayah mental, Ibn Sînâ
menerima mâhiyâh lebih fundamental daripada wujûd163. Nantinya, Mullâ Sadrâ
https://www.cambridge.org/core/product/identifier/CBO9781844654642A011/type/book_pa
rt. 159 Jon McGinnis, “Scientific Methodologies in Medieval Islam,” Journal of the
History of Philosophy 41, no. 3 (2003): 307–327,
http://muse.jhu.edu/content/crossref/journals/journal_of_the_history_of_philosophy/v041/41
.3mcginnis.html. 160 Alparslan Açıkgenç, Being and Existence in Ṣadrā and Heidegger: A
Comparative Ontology (Kuala Lumpur: ISCAC, 1993), 21–23. 161 Seyyed Hossein Nasr, Islamic Philosophy From Its Origin to the Present (New
York: State University of New York Press, 2006), 65. 162 Izutsu, Struktur Metafisika Sabzawari, 47. 163 Seyyed Hossein Nasr, “Existence (Wujūd) and Quiddity (Māhiyyah) in Islamic
Philosophy,” International Philosophical Quarterly 29, no. 4 (1989): 409–428,
46
sepakat bahwa wujûd itu lebih fundamental daripada mâhiyâh, tetapi tidak sepakat
dengan klasifikasi wujûd perspektif Ibn Sînâ. Menurut Ibn Sînâ, wujûd itu
fundamental pada realitas eksternal. Setiap wujûd itu berbeda dalam setiap ekstensi
(huwiyah). Sementara bagi Mullâ Sadrâ, wujûd memang lebih fundamental pada
realitas eksternal, sekaligus merupakan satu entitas tunggal yang bergradasi menjadi
tiap-tiap ekstensi, menjadi berbeda hingga munculnya keberagaman ekstensi akibat
perbedaan mâhiyâh yang diproyeksi mental164.
Bila al-Fârâbî membagi wujûd kepada dua bagian, Ibn Sînâ membagi wujûd
pada tiga bagian, yakni Wajîb al-Wujūd, mumkin al-wujūd, dan mumtanî al-wujūd.
Alasannya, tiga bagian wujûd inilah yang dapat dibentuk penalaran manusia.
Mumtanî al-wujûd adalah konsep wujûd yang mustahil memiliki acuan pada realitas,
seperti syarik al-bârî, atau sekutu Tuhan165. Wajîb al-Wujūd adalah wujûd yang
mengada karena dirinya sendiri. Mumkin al-wujūd adalah wujûd yang hanya
mengandung potensialitas untuk menjelma, dan hanya dapat menjelma ketika
diberikan wujûd oleh Wajîb al-Wujūd. Oleh karena itu, dalam konsep Ibn Sînâ, Wajîb
al-wujûd itu terbagi dua, yakni Wajîb al-Wujûd lî nafsihî, yakni yang memberikan
wujûd kepada mumkin al-wujûd dan wajîb al-wujûd lî ghayrihî, yakni wajîb al-wujûd
yang diberikan wujûd oleh Wajîb al-Wujûd bî nafsihî166.
Ibn Sînâ mengatakan bahwa mâhiyâh terbagi dua, yakni mâhiyâh yang menjadi
jawaban terhadap setiap pertanyaan “apa itu?”, dan mâhiyâh yang tidak berpisah
dengan wujûd, yakni apa yang dinisbahkan kepada Wajîb al-Wujûd bî nafsihî.
Sementara wajîb al-wujûd bî ghayrihî adalah wujûd yang eksistensinya tidak tetap,
wujûd yang tidak tetap itu menerima hukum gerak167. Dari kasus kesalahpahaman
para filosof dalam memaknai penjelasan Ibn Sînâ tentang fundamentalitas atau
kemendasaran (ashalat) wujûd atas mâhiyâh maka sangat penting dalam memahami
filsafat untuk membedakan antara wilayah konseptual dan wilayah realitas. Hal ini
misalnya agar dapat dengan jelas memaknai bagaimana penjelasan tentang konsep
wujûd dan bagaimana penjelasan tentang realitas wujûd. Demikian juga dalam
memahami penjelasan tentang gerak.
Ibn Sînâ berpandangan, secara konseptual, gerak adalah abstraksi pikiran atas
dua momen waktu. Sementara dalam realitas eksternal, gerak terjadi pada beberapa
bagian aksiden, yakni kualitas, kuantitas, posisi, dan tempat. Gerak itu terkait dengan
enam perkara, yakni subjek yang bergerak, sebab penggerak, lokasi gerak, asal gerak,
tujuan gerak, dan waktu sebagai ukuran ukuran yang diabstraksi dari perpindahan
sesuatu yang bergerak168. Kausalitas muncul dari pengamatan atas gerak. Bagi Ibn
Sînâ, perubahan dari beberapa aksiden yang terlibat dalam hukum gerak itulah yang
http://www.pdcnet.org/oom/service?url_ver=Z39.88-
2004&rft_val_fmt=&rft.imuse_id=ipq_1989_0029_0004_0409_0428&svc_id=info:www.pd
cnet.org/collection. 164 Susilo, “Teori Gradasi : Komparasi Antara Ibn Sina, Suhrawardi Dan Mulla Sadra.” 165 Mulyadhi Kartanegara, Menembus Batas Waktu: Panorama Filsafat Islam, 2005,
34–35. 166 Hanafi, Filsafat Islam, 126. 167 Syah Reza, “Konsep Nafs Menurut Ibnu Sina,” Kalimah 12, no. 2 (September 15,
2014): 263, http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah/article/view/239 168 Hanafi, Filsafat Islam, 131–132.
47
dianggap sebagai gerak169. Sementara substansi, tidak dianggap bergerak karena bila
substansi bergerak, itu tidak dapat disebut sebagai gerak karena itu adalah persoalan
tentang dua ekstensi170.
Jiwa sebagai manifestasi wujûd dalam pandangan Ibn Sînâ sebagai bagian dari
substansi tidak terlibat hukum gerak. Menurutnya, jiwa hanya menjadikan jasad
sebagai instrumen, persis seperti masinis yang menggerakkan kereta api. Sebab itulah
jiwa dikatakan baru hadir kepada jasad setelah jasad itu sempurna sehingga definisi
Ibn Sînâ atas jiwa adalah kesempurnaan pertama jasad171. Definisi ini dibangun
berdasarkan argumentasi bahwa sekalipun mengalami terjadi reduksi pada jasad,
seperti putusnya bagian tertentu dari jasad, pengetahuan tentang diri tetap utuh172.
Maka dari itu, kesempurnaan jasad yang dimaksud adalah kesempurnaan pertama
jiwa karena jiwa setelah berpisah dengan jasad masih terus menempuh perjalanan
penyempurnaan tanpa henti173.
Ibn Sînâ membuat delapan daya jiwa yang terbagi kepada tiga pembagian.
Sembilan daya jiwa itu adalah daya menyerap nutrisi, daya tumbuh, daya reproduksi,
daya gerak dengan kehendak, daya persepsi, daya imajinasi, daya estimasi, dan daya
inteleksi. Daya pertama hingga ketiga dimiliki tumbuhan, daya pertama hingga
ketujuh dimiliki hewan. Hanya manusia yang memiliki delapan daya itu. Dengan
memiliki daya inteleksi maka manusia menjadi makhluk paling unik. Daya inteleksi
adalah daya akal manusia. Daya berpikir ini terbagi menjadi berpikir praktis, yakni
berpikir untuk tindakan dan daya akal teoretis. Akal teoretis terbagi kepada empat,
yakni akal hayūla, yakni potensi berpikir yang belum diaktualkan untuk berpikir, akal
malakūt, yakni akal yang dilatih untuk menerima hal-hal abstrak, akal aktual
digunakan untuk berfikir hal-hal abstrak, dan akal mustafad, yakni akal yang mampu
menerima limpahan Wujûd Akal Aktif174.
Dalam pandangan Ibn Sînâ, jiwa dan jasad adalah dua substansi terpisah.
Dengan demikian, apabila jasad hancur, wujûd jiwa leluasa keluar dari jasad, seperti
pada kasus kematian. Menurut Ibn Sînâ, nantinya yang berbangkit pada hari kiamat
adalah jiwa saja175. Pandangan ini ditentang keras oleh teolog, seperti Abû Hamid al-
Ghazalî176. Kecaman lainnya kepada Ibn Sînâ adalah pandangannya tentang sumber
169 Miswari, Filsafat Terakhir, 146–147. 170 Kiki Kennedy-Day, “Ibn Sina,” in Books of Definition in Islamic Philosophy
(Abingdon, UK: Taylor & Francis, 2010), 51,
https://www.taylorfrancis.com/books/9780203221372. 171 Sînâ, Ibn, al-Nafs min Kitâb al-Syifâ, (Qum: Markaz al-Nasyr-Maktab al-I‟lâm al-
Islâmî, 1417 H.), 28-29.
172 Nusution, Harun, Falsafat dan Mistisme dalam Islam: Filsafat Islam, Mistisme
Islam, dan Tasawuf (Jakarta: Bulan Bintang, 2018), 23. 173 Hanafi, Filsafat Islam, 133. 174 Sînâ, Ibn, al-Nafs min Kitâb al-Syifâ, 32-35. 175 Sînâ, Ibn, al-Nafs min Kitâb al-Syifâ, 28-29; Inati, “Ibn Sina,” 236. 176 Farouk Mitha, Al-Ghazali and the Ismailis: Debate on Reason and Authority in
Medieval Islam (London & New York: I.B. Taurus Publisher, 2001), 86–88.
48
kejadian semesta177. Abû Hamid al-Ghazalî bersikeras bahwa wujûd alam semesta
terjadi dalam waktu, dari ketiadaan karena bila tidak, semesta itu kekal, telah azali
bersama Wujûd Tuhan, dan ini mustahil karena tidak ada yang azali, selain Wujûd
Tuhan178. Menurut Ibn Sînâ, semesta terjadi bukan dari ketiadaan, melainkan dari
sesuatu yang telah mengada179. Pandangan demikian karena dalam kaidah filsafat,
yang tidak memiliki mustahil dapat memberikan. Maksudnya, dari ketiadaan
mustahil menjelma keberadaan, seperti semesta. Penentangan kalam lainnya dari Abû
Hamid al-Ghazalî atas filsafat Ibn Sînâ adalah tentang pengetahuan Tuhan tentang
partikular180. Menurut Abû Hamid al-Ghazalî, Tuhan dapat mengetahui hal-hal detail
yang diketahui manusia. Menurut Ibn Sînâ, Tuhan tidak mengetahui hal-hal detail
seperti pengetahuan manusia karena bila Tuhan mengetahui hal-hal detail seperti
manusia, pengetahuan Tuhan sama seperti pengetahuan manusia. Dan itu mustahil.
Abû Hamid al-Ghazalî adalah salah seorang pemikir yang sangat menguasai filsafat.
Dia mampu menggugat dalil-dalil filsafat dengan cukup baik. Pemahamannya
tentang filsafat juga terbukti sangat baik, setidaknya untuk bidang logika dibuktikan
dalam Mi’yâr al-‘Ilm fî al-Manthiq’ dan pemahaman tentang epistemologi dibuktikan
dengan karya al-Maqasit al-Falasifah. Buku itu ditulis sebagai persiapan untuk
mengkritik aliran filsafat al-Hikmah al-Masyâ'iyyah181.
Pemikir selanjutnya yang berkaitan erat dengan pemikiran Mullâ Sadrâ adalah
Syihab al-Dîn al-Suhrawardî. Menurut Ziai182, Syihab al-Dîn al-Suhrawardî,
berseberangan dengan al-Hikmah al-Masyâ'iyyah, mengganti terminologi wujûd Ibn
Sînâ dengan analogi cahaya. Wujûd al-Wajîb lî Nafsîhî diistilahkan dengan Nûr al-
Anwar (Cahaya Segala Cahaya). Sementara tingkatan-tingkatan inteleksi diganti
dengan anwar al-mujarradah (intelek-intelek abstrak)183. Menurut Syihab al-Dîn al-
Suhrawardî, pengetahuan yang akurat berasal dari dalam diri184. Pengetahuan ini
memang mirip dengan pengetahuan yang diakui sufi. Namun uniknya, pemahaman
ini ditemukan Syihab al-Dîn al-Suhrawardî melalui pertemuan dengan Aristoteles
melalui mimpi. Hossein Ziai mengatakan, kehadiran Syihab al-Dîn al-Suhrawardî
adalah simbol kemenangan Platonisme atas Aristotelianisme185.
Akurasi pengetahuan berbasis kesadaran menjadi semangat Syihab al-Dîn al-
Suhrawardî mengkritik landasan dasar Peripatetik, yakni definisi. Definisi adalah
rumusan yang menunjukkan esensi dan unsur penyusunnya. Menurut Syihab al-Dîn
al-Suhrawardî, pendefinisian sesuatu mensyaratkan pemahaman atas alat yang
177 Qadir, C.A., Philosophy and Science in The Islamic World (London & New York:
Routledge, 2013), 82. 178 Sheikh, Islamic Philosophy, 87–88. 179 Madjid Nurcholish, Ibn Taimiyah tentang Kalam dan Falsafah, (Jakarta,
Nurcholish Madjid Society, 2020), 149-150. 180 Louay Safi, The Foundation of Knowledge (Selangor: IIUM Press, 1996), 96. 181 Safi, The Foundation of Knowledge, 96. 182 Ziai, “Shihab Al-Din Suhrawardi: Founder of the Illuminationist,” 434. 183 Ziai, Suhrawardi Dan Filsafat Illuminasi,,,, 225–227. 184 Syihab al-Dîn Suhrawardî, “Hikmah Al-Isyrâq,” dalam Majmû’ah Muśannafât
Syaikh Al-Isyrâq Vol. II (Teheran: Pezhuhesgâh „Olûm-e Insânî va Moțâla‟ât-e Farhangge,
1979), 11. 185 Ziai, “Shihab Al-Din Suhrawardi: Founder of the Illuminationist,”…, 437.
49
digunakan untuk mendefinisikan sesuatu. Misalnya, mendefinisikan “manusia”
dengan 'manusia adalah hewan yang berpikir'. Definisi ini mensyaratkan pengetahuan
apa itu “berpikir”. Bila “berpikir” belum diketahui, perlu lebih dahulu mendefinisikan
apa itu “berpikir”. Lalu, bila ingin mendefinisikan berpikir, diperlukan bekal
pengetahuan akan alat yang digunakan untuk mendefinisikan “berpikir”. Misalnya,
berpikir adalah 'suatu kegiatan jiwa’. Maka dari itu, definisi ‘suatu kegiatan jiwa’
perlu diketahui lebih dahulu. Demikian seterusnya.
Sebenarnya, definisi Aristotelian lebih mengutamakan pengetahuan atas esensi
yang ingin diketahui. Hakikat “manusia” adalah “berpikir”. Maka dari itu, “berpikir”
itulah fokusnya. Sementara “hewan” bagi manusia malah makin mengaburkan
penjelasan tentang manusia. Sebenarnya, hakikat “berpikir” itulah esensi “manusia”.
Akan tetapi, itu terbukti tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, menurut filsafat
Syihab al-Dîn al-Suhrawardî, dasar epistemologi Peripatetik menjadi tertolak karena
hanya melalui definisi, proposisi, dan silogisme pengetahuan dibangun186. Baik
melalui induksi maupun deduksi, penalaran menjadi tidak bermakna karena premis-
premis hanya dapat dibangun apabila definisi telah dapat diterima. ‘Semua manusia
akan mati’ sebagai premis mayor, ‘Aristoteles adalah manusia’ sebagai premis minor
maka Aristoteles pasti mati, sebagai contoh penalaran deduktif menjadi tidak
bermakna ketika definisi “manusia” belum tuntas187.
Karena definisi mensyaratkan pengetahuan, sementara definisi Aristotelian
menurut Syihab al-Dîn al-Suhrawardî dan sebagian filosof lainnya tidak mampu
menghadirkan pengetahuan maka itu berarti mensyaratkan suatu pengetahuan yang
telah terbukti dengan sendirinya. Pengetahuan yang dimaksud tidak membutuhkan
definisi. Karena telah terbukti dengan sendirinya. Pengetahuan demikian diistilahkan
oleh Syihab al-Dîn al-Suhrawardî dengan visi Illuminasi yang dianalogikan dengan
cahaya. Analogi cahaya digunakan karena tidak ada yang lebih terang daripada
cahaya. Apa pun yang digunakan untuk mendefinisikan cahaya tidak berguna. Karena
tidak ada yang telah lebih terang daripada cahaya. Pengetahuan ini sangat jelas karena
terbukti dengan sendirinya. Pengetahuan ini diperoleh melalui pengalaman atau
penglihatan langsung188. Syihab al-Dîn al-Suhrawardî mengatakan, untuk
memunculkan kesadaran diri sebagai prasyarat pengetahuan sejati (al-'ulum al-
haqiqiyyah).
Bagi Syihab al-Dîn al-Suhrawardî, pengetahuan akurat harus sebagai sesuatu
yang menyeluruh, tidak parsial atau tidak rangkap. Maksudnya, misalnya 'manusia
adalah hewan yang berpikir' adalah gabungan beberapa term, yang bila diasumsikan
setiap termnya memiliki acuan maka itu berarti rangkap189. Pengetahuan tentang
sesuatu mensyaratkan kesadaran diri yang mengetahui (pengetahu, mudriq). Bagi
186 Suhrawardi, “Hikmah Al-Isyrâq”, 13. 187 Husein Heriyanto, Refleksi Kritis Terhadap Persepsi Populer tentang Logika
Modern dan Indonsivisme (Jakarta, 2019), 3–4. 188 Yazdi, The Principles of Epistemology in Islamic Phlosophy: Knowledge by
Presence…, 36. 189 Muhammad Muslih, “Kesadaran Intuitif Plus Cahaya Ilahiyah: Husserl Di Muka
Cermin Suhrawardi,” TSAQAFAH 5, no. 1 (May 31, 2009), 29,
http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/146.
50
Syihab al-Dîn al-Suhrawardî, baik itu Sumber Cahaya maupun pancaran-
pancarannya memiliki kesadaran diri, kecuali yang sama sekali tidak memiliki
pancaran cahaya (kegelapan).
Syihab al-Dîn al-Suhrawardî mengganti sistem akal (inteleksi) yang mencapai
‘aql mustafad yang memperoleh pengetahuan dari akal aktif dengan gagasan cahaya.
Gagasan cahaya diperoleh melalui visi dan illuminasi. Visi adalah persiapan diri
untuk mencapai pengetahuan langsung. Visi terjadi ketika Nûr al-Anwâr menyinari
(iluminasi) segala sesuatu sehingga visi dan iluminasi adalah satu kesatuan yang tidak
terpisah. Pengetahuan manusia dalam sistem ini terjadi karena kesadaran diri melalui
prinsip cahaya yang mengendalikan (al-anwâr al-qahirah) dan cahaya yang
mengatur (al-anwâr al-mudabbirah) yang datang dari Nûr al-Anwâr190. Pengetahuan
yang hadir kepada manusia dalam sistem ini disebut cahaya al-isfahbat. Pengalaman
ini disebut cahaya apokaliptik (al-anwâr al-sanihah)191. Ajaran Syihab al-Dîn al-
Suhrawardî selanjutnya diteruskan oleh Qutb al-Dîn Shirazî dan gurunya Mullâ
Sadrâ, Mîr Dâmâd.
Sistem pengetahuan langsung melalui kesadaran diri yang dibuat Syihab al-
Dîn al-Suhrawardî dapat dikatakan memberikan inspirasi bagi Mullâ Sadrâ dalam
merumuskan konsep kesatuan subjek dan objek (ittihad aqil wa ma'qul). Akan tetapi,
konsep Mullâ Sadrâ itu lebih mirip dengan gagasan Ibn 'Arabî. Filsafat Syihab al-Dîn
al-Suhrawardî sebenarnya sangat memengaruhi Mullâ Sadrâ, khususnya tentang
bagaimana seorang filosof yang baik harus memiliki keluasan batin dan kemampuan
penalaran yang baik. Sementara Mullâ Sadrâ mengkritik Syihab al-Dîn al-Suhrawardî
tentang kemendasaran mâhiyâh. Bagi Syihab al-Dîn al-Suhrawardî, mâhiyâh menjadi
dasar pembentukan realitas. Sementara Mullâ Sadrâ berpendapat sebaliknya, yakni
mengatakan wujûd adalah yang fundamental.
B. Teori Wujûd dalam Wujudiah
Ajaran tasawuf tidak bisa dilepaskan dari perdebatannya dalam tiap-tiap varian
dan bahkan antar sufi dalam satu varian terkadang memiliki perbedaan pemikiran.
Pemikiran tasawuf dalam Islam perlu digali akarnya dari mistisme yang bahkan telah
berkembang di luar dunia Islam. Kata “diam” memiliki akar kata mou yang menjadi
dasar kata mysterion, kemudian diadopsi oleh kosakata Inggris menjadi mystery dan
juga dipadankan dengan mysticism. Selanjutnya, kata mysticism diadopsikan ke
dalam bahasa Indonesia menjadi kata “mistisme” atau “mistisisme”192. Mistisme
selalu hidup dalam berbagai tradisi sejauh manusia menyadari bahwa terdapat aspek
transenden yang menguasai seluruh jagat semesta. Para pengkaji mistisme, baik di
Timur maupun di Barat mengkaji kesamaan-kesamaan dalam tradisi ini melalui
kesamaan-kesamaan yang dapat ditarik dari berbagai pernyataan dari berbagai aliran.
Namun sebenarnya, persamaan penting antar aliran mistisme itu adalah pada
kesamaan potensi manusia, yakni sebagai makhluk spiritual. Mistisme dalam ajaran
Hindu mengandung simbol-simbol yang unik sebagai alat komunikasi ajarannya.
190 Suhrawardî, “Hikmah Al-Isyrâq,”, 11-12. 191 Ziai, Suhrawardi dan Filsafat Illuminasi, 225–227. 192 Ahmad Saifuddin, Psikologi Agama: Implementasi Psikologi untuk Memahami
Perilaku Agama (Jakarta: Kencana, 2019), 111.
51
Dalam agama Yahudi, mistisme juga memiliki pengaruh yang mendasar. Dalam
agama Kristen, mistisme digali dari ajaran Yahudi dan Nasrani sendiri serta
melibatkan berbagai sombol dari ajaran Hindu. Dalam Islam fokus ajaran mistisme
dikembangkan oleh kaum sufi193.
Terminologi mistisme dipadankan dengan sikap kaum sufi yang menjadi
penjaga misteri (asrâr) Wujûd Ilahi. Misteri Wujûd Ilahi adalah rahasia yang dijaga
kaum sufi atas pengetahuan (ma'rifâh) tentang Wujûd Haqq Ta’ala194. Aktivitas
mereka juga disebut dengan ‘irfân dan para sufi disebut dengan 'arîf (tunggal) atau
'urafâ (jamak). Dalam tradisi dunia Melayu, ajaran tasawuf bercorak filosofis yang
berpandangan pada kesatuan wujud (wahdah al-wujûd) disebut dengan Wujudiah.
Ajaran Wujudiah juga merupakan bagian dari ajaran tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi
juga disebut sebagai tasawuf teoretis karena menggunakan pendekatan teori dalam
pembahasan ajarannya. Teori yang digunakan bercorak filosofis sehingga disebut
tasawuf falsafi atau disebut juga tasawuf filosofis.
Istilah tasawuf sendiri berasal dari kata shûfah yang berarti mantel bulu dari
kain wol. Istilah itu diambil dari sifat sufi yang pasrah seperti mantel yang
dibentangkan. Ada juga pendapat bahwa tasawuf itu berasal dari kata ‘shifâh’ yang
berarti sifat untuk menjelaskan sifat terpuji dan mulia yang dipraktikkan kaum sufi195.
Dalam Islam, tasawuf, khususnya tasawuf Wujudiah, tidak berkembang dengan baik
karena banyak faktor196. Umumnya karena anggapan sulitnya memahami teori dan
pendekatan ajaran tersebut197. Praktik-praktik yang mereka lakukan juga dianggap
ekstrem oleh sebagian masyarakat sehingga tidak banyak yang bersedia menempuh
jalan spiritual itu. Mereka yang sedikit itu juga tidak banyak yang mampu
menuntaskan perjalanan-perjalanan spiritual. Faktor-faktor ini membuat tasawuf
Wujudiah menjadi tidak arus utama198.
Wujudiah adalah ajaran tasawuf bercorak filosofis yang dikembangkan oleh
kaum sufi sejak generasi awal perkembangan pemikiran Islam. Istilah “wujudiah”
dikembangkan dalam tradisi kajian tasawuf filosofis tentang ajaran wahdah al-wujûd
dalam diskursus berbahasa Melayu. Asal katanya adalah wujûdiyah, yakni sebuah
193 R.C.Zaehner , Mistisisme Hindu Muslim (Yogyakarta: LKiS, 2004), vii. 194 Seyyed Hossein Nasr, “Introduction to Mystical Tradition,” dalam History of
Islamic Philosophy Vol. I, ed. Seyyed Hossein Nasr dan Oliver Leaman (London & New
York: Routledge, 1996), 367. 195 Abdul Qadir Isa, Hakekat Tasawuf (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 7. 196 Humaidi, “Mystical-Metaphysics: The Type of Islamic Philosophy in Nusantara in
the 17th-18th Century,” Jurnal Ushuluddin 27, no. 1 (July 30, 2019): 90, http://ejournal.uin-
suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/5438. 197 Para sufi yang nama-nama mereka disebutkan dan pernyataan-pernyataan mereka
(syatahat) dikutip Hamzah Fansûrî dalam al-Muntahî adalah sufi falsafi ('urafâ). Di antara
nama-nama tersebut antara lain ‘Ain al-Qudat al-Hamadanî, Abû Mansûr al-Hallaj, ‘Abd al-
Rahman Jâmî, dan beberapa lainnya. Lihat, Hamzah Fansûrî, “Al-Muntahî,” dalam The
Mysticism of Hamzah Fansuri, oleh Syed Muhammad Naquib Al-Attas (Kuala Lumpur:
University of Malaya Press, 1970), 329–353. 198 Septiawadi, Septiawadi, “Pergolakan Pemikiran Tasawuf Di Indonesia: Kajian
Tokoh Sufi Ar-Raniri,” KALAM 7, no. 1 (March 2, 2017): 183,
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/view/448.
52
ajaran tasawuf yang menekankan pada diskursus tentang wujûd yang satu hanya
dinisbahkan kepada Haqq Ta’ala. Ajaran tersebut dibedakan dengan ajaran tasawuf
yang menekankan pada perbaikan amal atau disebut tasawuf amal. Corak tasawuf
amal juga dipadankan dengan tasawuf akhlak karena fokus pada perbaikan tingkah
laku yang baik. Namun, ajaran Wujudiah juga sebenarnya tetap menekankan pada
pengamalan dan akhlak. Akan tetapi, dari ajaran Wujudiah, yang paling dikenal
adalah ajaran kesatuan wujûd sehingga lebih dikenal dengan istilah Wujudiah.
Tradisi ajaran Wujudiah telah dikembangkan sejak periode awal
perkembangan Islam. Di Indonesia, ajaran tersebut dikembangkan oleh Hamzah
Fansûrî dilanjutkan oleh Shams al-Dîn al-Sumatranî dan ditentang oleh Nûr al-Dîn
al-Ranîrî. Nama terakhir ini sebenarnya tidak menentang ajaran Wujudiah secara
keseluruhan. Nûr al-Dîn al-Ranîrî tidak menentang ajaran Wujudiah Ibn ‘Arabî yang
dianggap lurus (muwahid). Dia hanya menentang Wujudiah Hamzah Fansûrî dan
Shams al-Dîn al-Sumatranî. Selain karena menggunakan analogi yang dianggap
kontroversial, ajaran Wujudiah dua sufi Melayu itu dianggap telah menyerap ajaran
Wujudiah yang dikembangkan, antara lain, oleh Abû Mansûr al-Hallaj dan Abû
Yazid al-Bistamî yang oleh Nûr al-Dîn al-Ranîrî dan umumnya mutakallimȋn
dianggap sesat (mulhith).
Hamzah Fansûrî mengembangkan ajaran Wujudiah di Kepulauan Indonesia
dalam gaya bahasa Melayu yang sangat indah dan ilmiah. Sejauh yang telah dapat
dianalisis oleh para pengkajinya, setidaknya Hamzah Fansûrî telah menghasilkan
sekitar tiga puluh karya berbentuk puisi dan tiga karya dalam bentuk prosa. Ajaran
Hamzah Fansûrî ditentang keras oleh Nûr al-Dîn al-Ranîrî karena dua alasan penting,
yakni menggunakan analogi yang dianggap mengarahkan pada kesesatan dan
menerima ajaran sufi kontroversial, seperti Abû Mansûr al-Hallaj.
Dalam sistem pengetahuan Wujudiah, pengetahuan menuju pengenalan Wujûd
Haqq Ta’ala adalah melalui perjalanan jiwa mulai jiwa rendah (al-nafs al-ammârah),
jiwa terilhami (al-nafs al-mulhamah), jiwa damai (al-nafs al-muthmainnah), jiwa
tulus (al-nafs al-radhiyyah), jiwa yang diridhai (al-nafs al-ardhiyyah), sampai
dengan jiwa sempurna (al-nafs al-kâmilah). Selanjutnya, menuju pembersihan roh
dengan mencapai pusat batiniah hati (qalb), roh (rūh), rahasia (sirr), rahasia dari
rahasia (sir al-sirr), tersembunyi (khifâ), dan sangat tersembunyi (akhfa). Bagian
sangat tersembunyi inilah yang menerima Realitas Wujûd Ilahi untuk mencerahkan
penempuh perjalanan spiritual (sâlîk)199. Penempuh jalan spiritual harus melalui
latihan kerendahan hati, penafian diri, ilham, kedamaian hati, kebahagiaan, diridai,
dan kesempurnaan. Sebenarnya, jalan-jalan yang ditempuh dalam jalan spiritual
tasawuf falsafi tidak terlalu bermasalah. Ungkapan-ungkapan ganjil (syatahat) yang
muncul dari mulut para penempuh jalan ini menjadi partisipator utama resistansi
sebagian ulama dan masyarakat umum atas Wujudiah200.
Alasan lain yang membuat sebagian aliran berbeda dengan Wujudiah dalam
memahami wujûd adalah karena mereka menggunakan penafsiran batin (esoteris)
199 Mahmud Erol Kilic, “Mysticism,” in History of Islamic Philosophy Vol. II, ed.
Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman (London & New York: Routledge, 1996), 947. 200 Rivay Siregar, Dari Sufisme Klasik ke Neo-Sufisme (Jakarta: Rajawali Press, 2002),
141–142.
53
terhadap ayat-ayat Al-Qur’an201. Di samping itu, hadis-hadis yang digunakan sufi
Wujudiah dalam memahami wujûd juga kurang familier bagi mutakallimîn dan
fuqâhâ. Para pengkaji hadis juga umumnya mengeluarkan pernyataan bahwa hadis-
hadis yang kerap digunakan ‘urafâ adalah tidak termasuk hadis sahih202. Hadis-hadis
yang dikemukakan urafâ adalah yang memuat pesan cinta Tuhan, yang menyatakan
bahwa Tuhan mencintai hamba-Nya sehingga Dia menjadi pendengaran ketika
mendengar. Allah juga memesankan bahwa Wujûd Allah adalah harta tersembunyi.
Dia menciptakan hamba agar Dia dikenal. Dikatakan pula bahwa Haqq Ta’ala
menjadikan manusia dalam bayangan Wujûd-Nya203.
Dalam ajaran Wujudiah, dikenal konsep fânâ. Konsep ini adalah kondisi
hilangnya kedirian seseorang dan melebur bersama Wujûd Haqq Ta’ala. Dalam
keadaan ini, seorang salîk kehilangan daya indranya. Penglihatannya melalui
perasaan. Syatahat bisa terlontarkan tanpa sadar dalam keadaan ini204. Yang dirasa
hanya Wujûd Haqq Ta’ala. Untuk mendapatkan pengalaman ini, latihan-latihan
tertentu dapat saja dilakukan. Akan tetapi, pengalaman ini adalah karunia Allah205.
Tahap selanjutnya yang dapat dicapai seorang salik adalah menyatu (ittihad)
dengan Wujûd Haqq Ta’ala. Konsep ittihad digagas oleh Abû Yazid al-Bistamî.
Manusia yang berasal dari Haqq Ta’ala dapat kembali bersatu dengan-Nya ketika
tidak lagi memiliki ketertarikan dengan dunia. Dalam keadaan ini, seorang salik
menjadi tidak dapat lagi mengidentifikasi wujûd dirinya. Yang terasa hanya Wujûd
Haqq Ta’ala yang Tunggal. Posibilitas menyatunya manusia dengan Haqq Ta’ala
karena manusia, selain sebagai wujûd jasmani, juga sebagai wujûd rohani.
Manusia adalah makhluk yang memiliki aspek wujûd jasmani dan aspek wujûd
rohani. Aspek wujûd jasmani disebut dengan nâsut atau aspek kemanusiaan.
Sementara aspek wujûd ruhani disebut dengan lâhût atau aspek ketuhanan. Ketika
manusia membersihkan diri dari aspek kemanusiaannya, Wujûd Tuhan
bermanifestasi (hûlûl) ke dalam diri manusia. Konsep ini dinisbahkan kepada Abû
Mansûr al-Hallaj206. Konsep yang dibangun tentang nâsut dan lâhût berdasarkan
pemahaman bahwa manusia diwujudkan dari gambar (sûrah) Wujûd Tuhan. Malaikat
diperintahkan sujud kepada Adam (manusia) karena Wujûd Haqq Ta’ala telah
menjelma dalam diri Adam.
201 Muhammad Nur Jabir, “Takwil Dalam Pandangan Mulla Sadra,” Kanz
Philosophia : A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism (2012), 291. 202 Kerwanto, “Manusia Dan Kesempurnaannya (Telaah Psikologi Transendental
Mullā Shadrā)”; Kerwanto Kerwanto, “Pemikiran Filosofis Sadra Dalam Tafsir Al-Qur’an Al-
Karim : Surah Al-’A‘La,” Kanz Philosophia : A Journal for Islamic Philosophy and
Mysticism 4, no. 2 (December 25, 2014): 23–50,
http://journal.sadra.ac.id/index.php/kanzphilosophia/article/view/63. 203 Wahid Bakhsh, Sufisme Islam (Jakarta: Sahara Publisher, 2004), 84. 204 Dzikrullah Zulkarnain, “Syaţaḥat Kaum Sufi: Sebuah Telaah Psikologis: Sebuah
Telaah Psikologis,” SMART 1, no. 1 (June 10, 2015): 77–110,
http://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/smart/article/view/232. 205 Izutsu, Struktur Metafisika Sabzawari, (Bandung: Pustaka, 2003), 16. 206 Miswari, “Cara Gila Jatuh Cinta: Analisa Qasidah Dan Muqataat Mansur Al-
Hallaj,” Al-Mabhats 4, no. 1 (2019): 51–74.
54
Menurut Ibn Farîd, sebagaimana dikemukakan oleh Fenton, tasawuf adalah
adalah ilmu sekaligus latihan diri207. Dalam tasawuf, manusia dianjurkan untuk
bersikap wâra', qana’ah, dan zûhûd. Proses menjaga diri ditempuh dengan suluk.
Dalam suluk terdapat berbagai tahapan latihan diri yang berat. Tahapan-tahapan
latihan dalam suluk tidak akan dapat dilalui, kecuali dengan cinta. Hanya bagi orang-
orang yang penuh dengan cinta dan kerinduan kepada Tuhan di dalam dirinya yang
mampu menempuh tahapan-demi tahapan dalam melatih diri208. Tasawuf Ibn Farîd
digolongkan sebagai Wahdah al-Syûhûd209. Penganut Wahdah al-Syûhûd lainnya
adalah 'Alâ al-Daulah al-Simmananî. Dalam pandangannya, dunia memiliki dua
makna sekaligus. Pertama, ia tidak memiliki eksistensi karena hanya sebagai
bayangan. Pada saat yang sama memiliki eksistensi karena dia adalah pancaran
ketuhanan. Kaum sufi mengaku bahwa sebenarnya Tuhan lebih dekat dengan
manusia melebihi dirinya sendiri. Tuhan adalah Wujûd yang lahir sekaligus yang
batin. Dia adalah yang awal sekaligus yang Akhir sehingga sufi meyakini bahwa
Wujûd yang nyata Tuhan saja. Ambiguitas memang telah menjadi prinsip dalam
ajaran sufi210. Ajaran tasawuf sebagaimana diajarkan Ibn Farîd dan 'Alâ al-Daulah al-
Simmananî dalam studi tasawuf dibedakan dengan Wahdat al-Wujûd sebagaimana
dikemukakan oleh Kautsar Azhari Noer211. Akan tetapi, menurut Haidar Bagir, secara
esensial, kedua ajaran ini memiliki kemiripan212. Bahkan, keseluruhan ajaran tasawuf
filosofis atau Wujudiah secara umum dapat dikatakan merupakan ajaran kesatuan
wujûd. Ajaran Wujudiah adalah ajaran tasawuf yang memiliki dalil dalam Al-
Qur’an213. Di antaranya adalah Al-Qur’an 2 (Al-Baqarah): 115, Al-Qur’an 2 (Al-
Baqarah): 186, Al-Qur’an 4 (al-Nisa’): 126, Al-Qur’an 8 (al-Anfāl): 17, Al-Qur’an
28 (al-Qisash): 88, Al-Qur’an 50 (Qāf): 16, Al-Qur’an 57 (al-Hadîd): 3; Al-Qur’an
58 (al-Mujādilah): 7.
Telah ada penelitian yang mengurai secara detail ayat-ayat yang menjadi
sumber rujukan sufi umumnya, khususnya ajaran Wujudiah214. Al-Qur’an 2 (Al-
Baqarah): 115 yang berbunyi ''Milik Allah timur dan barat, maka ke mana pun kamu
menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha
Mengetahui.'' Sufi memaknai ayat ini secara lahiriah menjadi lebih jelas, yakni dua
arah, maghrib dan masyriq dengan enam arah, yakni atas, bawah, kiri, kanan, depan,
207 Paul B. Fenton, “Judaism and Sufism,” in History of Islamic Philosophy Vol. I, ed.
Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman (London & New York: Routledge, 1995), 758. 208 Ainul Abidin Shah, “Epistemologi Sufi : Perspektif Al-Hakim Al-Tirmidzi,” Kanz
Philosophia : A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism 2, no. 1 (June 23, 2012): 153,
http://journal.sadra.ac.id/index.php/kanzphilosophia/article/view/28. 209 Fenton, “Judaism and Sufism,” 758. 210 Wahid Bakhsh, Sufisme Islam (Jakarta: Sahara Publisher, 2004), 93. 211 Kautsar Azhari Noer, “Tasawuf Dalam Peradaban Islam: Apresiasi Dan Kritik,”
Ulumuna 10, no. 2 (November 5, 2017): 367–390,
http://ulumuna.or.id/index.php/ujis/article/view/174. 212 Haidar Bagir, “Diskusi Pengalaman Religius,” Kanz Philosophia : A Journal for
Islamic Philosophy and Mysticism (2011), 129. 213 Muhammad Nur Jabir, Wahdah Al-Wujûd Ibn ‘Arabî Dan Filsafat Wujûd Mulla
Sadrâ (Makassar: Chamran Press, 2012), 3. 214 Nasution, “Waḥdat Al-Wujûd Dalam Alquran.”…, 258.
55
dan belakang. Karena Wujûd Haqq Ta’ala bukan genus dan bukan differensia, Shams
al-Dîn al-Sumatranî mengatakan tiada bagi Wujûd-Nya bagi dan tiada bagi-Nya rupa,
dan tiada bagi-Nya sekutu.215” Maka dari itu, Wujûd Haqq Ta’ala benar-benar
meliputi segala arah dan tidak tunduk pada arah mana pun serta tidak bertempat.
Namun demikian, Wujûd Haqq Ta’ala dapat bermanifestasi dalam hati penempuh
jalan spiritual manusia216.
Dalam Al-Qur’an 2 (Al-Baqarah): 186 yang berbunyi:
منوا بي لعلهم يرشدون ا سالك عبادي عن ي فان ي قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤ واذ
Artinya:
''Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang Aku, maka
sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang
berdoa apabila ia memohon kepada-Ku. Maka hendaklah mereka memenuhi-
Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada
dalam kebenaran.''
Makna batin yang ditangkap penempuh jalan spiritual dari ayat ini adalah
bahwa Wujûd Haqq Ta’ala bahkan lebih dekat daripada dirinya sendiri. Karena
itulah, makna kedekatan Wujûd Haqq Ta’ala berarti Dia melampaui segala sesuatu
karena hanya Wujûd Haqq Ta’ala saja yang nyata217. Sementara itu, dalam Al-Qur’an
50 (Qāf): 16 yang berbunyi:
نسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ولقد خلقنا ال
Artinya:
“Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui
apa yang dibisikkan hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya dari pada urat
lehernya.”
Ayat ini juga memiliki makna yang sama yakni pernyataan bahwa Allah itu
dekat. Adapun Al-Qur’an 4 (an-Nisa’): 126 yang berbunyi:
حيطا بكل شيء م ما فى السموت وما فى الرض وكان للاه ولله
Artinya:
''Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan adalah
Allah Maha Meliputi segala sesuatu.''
215 Hasjmy, Ruba’i Hamzah Fansûrî…, 26. 216Andi Herawati, “Concerning Ibn ’Arabi’s Account of Knowlegde of God (Ma’rifa)
Al Haqq,” Kanz Philosophia : A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism 3, no. 2
(December 25, 2013): 219,
http://journal.sadra.ac.id/index.php/kanzphilosophia/article/view/49. 217 Nasution, “Waḥdat Al-Wujûd Dalam Alquran,” 258–283.
56
Makna ayat ini begitu jelas bagi sufi bahwa seluruh jagat semesta hanya Wujûd
Haqq Ta’ala yang meliputinya. Sebab itulah, dalam pandangan ‘irfan, Wujûd mandiri
hanya Haqq Ta’ala, semesta hanyalah bayangan dari Wujûd-Nya.
Al-Qur’an 8 (al-Anfāl): 17 berbunyi:
رمى وليبلي المؤ قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن للاه فلم تقتلوهم ولكن للاه ء حسنا ان للاه منين منه بل
سميع عليم Artinya:
''Maka bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah yang
membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau
melempar, tetapi Allah yang melempar. Dia menganugerahkan kepada kaum
mukmin dari sisi-Nya anugerah yang baik.''
Ayat ini menunjukkan bahwa sebenarnya perbuatan-perbuatan manusia hanya
bersifat majasi. Pada realitasnya, segala tindakan itu adalah dari Haqq Ta’ala. Ayat
ini adalah salah satu ayat yang kerap digunakan sufi untuk menunjukkan bahwa
Wujûd sejati hanya Haqq Ta’ala, sementara yang lainnya hanya sebagai bentuk
metafora. Di samping itu, Al-Qur’an 28 (al-Qasash): 88 yang berbunyi:
الها اخر ل اله ال هو كل شيء هالك ال وجهه له الحكم واليه ترجعون ول تدع مع للاه
Artinya:
“Dan jangan menyembah bersama Allah, tuhan apa pun yang lain, tidak ada
Tuhan melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu binasa, kecuali Wajah-Nya. Bagi-Nya
segala penentuan, dan hanya kepada-Nya kamu dikembalikan.”
Dalam pandangan ‘urafa, suatu yang nyata hanya Wujûd Haqq Ta’ala, segala
kemajemukan yang terindrai dan yang dipersepsikan hanya wujûd yang bersifat
temporer. Sejatinya memang tidak memiliki wujûd yang nyata. Sementara yang nyata
hanyalah wajah (eksistensi) Haqq Ta’ala218. Dalam Al-Qur’an 57 (al-Hadîd): 3
tercantum:
وهو بكل شيء عليم خر والظاهر والباطن ل وال هو الو
Artinya:
“Dialah yang Awal dan yang Akhir dan yang Zahir dan yang Batin; dan Dia
menyangkut segala sesuatu Maha Mengetahui.”
Sufi berpendapat segala yang lahir dan yang batin tidak ada yang meliputi,
kecuali Wujûd Haqq Ta’ala. Namun, alam itu bukan Dia karena alam semesta
hanyalah bayangan dari pancaran Wujûd nyata Haqq Ta’ala219. Al-Qur’an 58 (Al-
Mujādilah): 7 yang berbunyi:
218 Saliyo, “Selayang Pandang Harmonisasi Spiritual Sufi dalam Psikologi Agama,”
Psikoislamika : Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam 11, no. 2 (December 30, 2014), 5-11
http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/6383. 219 Bakhsh, Sufisme Islam, 83.
57
يعلم ما فى السموت وما فى الرض ما يكون من نجوى ثلثة ال هو رابعهم ول خمسة ال الم تر ان للاه
بكل شيء هو سادسهم ول ادنى من ذلك ول اكثر ال هو معهم اين ما كانوا ثم ينب ئهم بم ا عملوا يوم القيمة ان للاه
علي
Artinya:
“Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit
dan apa yang ada di bumi; Tiada sedikitpun pembicaraan rahasia antara tiga
orang, melainkan Dia-lah keempat dan tiada lima orang, melainkan dialah yang
keenam mereka. Dan tiada pembicaraan antara yang lebih sedikit dari pada itu
atau lebih banyak, melainkan Dia bersama mereka di mana pun mereka berada.
Kemudian Dia akan memberikan kepada mereka apa yang telah mereka
kerjakan pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyangkut segala sesuatu
Maha Mengetahui.”
Dalam pemaknaan penganut Wujudiah, ayat ini menunjukkan bahwa segala
jumlah itu kembali kepada Haqq Ta’ala. Gambaran ini sesuai dengan pandangan Ibn
‘Arabî bahwa hakikat dalam tamsil angka hanya satu sementara angka-angka lainnya
kembali kepada angka satu sehingga dapat dikatakan bahwa segala kemajemukan
wujûd itu hanya artifisial semata. Sementara yang nyata hanyalah satu, yakni Wujûd
Haqq Ta’ala.
Wujudiah adalah ajaran sufi yang mencapai kesempurnaan konsepnya di
tangan Ibn Arabî. Akan tetapi, ajaran tersebut dapat dikatakan memiliki sejarah
panjang dalam tasawuf falsafi. Sufi generasi awal, seperti Rabi’ah al-Adawiyah dan
Sufyân al-Tsaurî berfokus pada penyucian diri tanpa melakukan analisis filosofis
terhadap ajarannya. Sementara itu, narasi filosofis baru dirintis oleh Dhu’nûn al-Misrî
dan Abû Yazid al-Bistamî. Selanjutnya, Abû Mansûr al-Hallaj menjadikan tasawuf
falsafi menjadi makin radikal. Syatahat-nya juga sangat ekstrem.
Dalam tasawuf Rabi’ah al-Adawiyah, keindahan melihat Wujûd Haqq Ta’ala
adalah sasaran ibadah. Dia mengatakan, apa pun karunia yang ingin diberikan kepada
dirinya di dunia, lebih baik dihibahkan kepada pecinta dunia. Apa pun karunia yang
ingin diberikan kepada dirinya di akhirat, lebih baik dipersembahkan kepada ahli
ibadah. Sementara Rabi’ah al-Adawiyah sendiri hanya ingin melihat Wujûd Haqq
Ta’ala, sebagaimana diungkapkan Rabi’ah al-Adawiyah sebagai berikut220.
Ya Ilahi, jika sekiranya aku beribadah kepada Engkau karena takut
akan siksa neraka, maka bakarlah aku dengan neraka-Mu.
Dan jika aku beribadah kepada Engkau karena harap akan masuk
surga, maka haramkanlah aku daripadanya.
Tetapi jika aku beribadah kepada Engkau hanya karena semata-mata
karena kecintaanku kepada-Mu, maka janganlah, Ya Illahi, Engkau haramkan
aku melihat keindahanmu yang azali.
Kezuhudan Rabi’ah al-Adawiyah menginspirasi banyak sufi lainnya, termasuk
sufi besar, seperti Sufyân al-Tsaurî (716–778). Dia adalah ahli hadis dan kâlâm yang
220 Solihin dan Rosihon Anwar, Ilmu Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 150.
58
lahir pada 715 M. Sufyân al-Tsaurȋ juga merupakan fuqâhâ yang memiliki sekolah
yang mempelajari hukum Islam. Dia memiliki banyak murid yang ahli fikih.
Kejeniusan Sufyân al-Tsaurî sangat dipengaruhi oleh motivasi yang diberikan
ayahnya. Keluarga Sufyân al-Tsaurî adalah orang-orang yang hidup wara' dan penuh
kezuhudan221.
Sufyân al-Tsaurî adalah pelopor sufi generasi awal. Kezuhudan dan penyucian
diri adalah prasyarat dalam jalan spiritual. Akan tetapi, Sufyân al-Tsaurî tidak
meninggalkan aktivitas sosial. Dia juga sibuk dengan mendidik keilmuan, fikih,
hadis, dan tasawuf. Keilmuan-keilmuan tersebut adalah fokus utama lembaga
pendidikannya. Lembaga tersebut berhasil melahirkan ulama besar. Di antaranya
adalah Imam Mâlik yang menjadi salah satu pendiri mazhab fikih. Bahkan, Imam
Malâk menjadi guru pada pendiri mazhab fikih lainnya, seperti Imam al-Syâfi'i222.
Namun dalam perkembangannya, tasawuf tidak hanya sebagai praktik
kezuhudan, namun juga kajian filosofis atas pengalaman-pengalaman spiritual yang
dialami. Kajian filosofis ini dimulai oleh Dhu’nûn al-Misrî (796–856). Dia adalah
seorang sufi yang memiliki karâmah. Dia pernah mengeluarkan seorang anak yang
dimakan buaya dengan selamat. Dhu’nûn al-Misrî belajar dan mengembara ke
tempat-tempat yang jauh. Dia juga pernah menuntut ilmu kepada Imam Ibn Hambal.
Akan tetapi, kecenderungannya pada tasawuf membuatnya dikenal sebagai seorang
sufi. Dhu’nûn al-Misrî adalah sufi generasi awal yang berkontribusi memperkenalkan
tasawuf secara filosofis. Dhu’nûn al-Misrî membedakan antara pengetahuan melalui
akal dan pengetahuan melalui hati. Menurutnya, pengetahuan yang sejati adalah
pengetahuan yang didapat melalui hati. Pengetahuan tersebut disebut ilmu makrifat.
Dhu’nûn al-Misrî menegaskan makrifat bukanlah pengetahuan tentang konsepsi
ketuhanan sebagaimana dipelajari teolog, dan bukan penalaran ketuhanan
sebagaimana dipelajari filosof. Pandangan Dhu’nûn al-Misrî tentang makrifat
menunjukkan identitas tasawuf yang berbeda dengan filsafat dan teologi223.
Kajian filosofis dalam tasawuf dilanjutkan oleh Abû Yazid al-Bistamî (804–
875) yang juga seorang sufi yang zuhud. Dalam pandangan Abû Yazid al-Bistamî,
seseorang dapat dikatakan sufi bukan karena keanehan, seperti melayang di udara.
Seseorang dianggap sufi ketika dia melakukan syariat dengan baik, dan menerapkan
akhlak sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah224. Abû Yazid al-Bistamî
menjadikan kehidupan Rasulullah sebagai barometer tasawuf yang dianutnya. Pernah
Abû Yazid al-Bistamî ingin berdoa supaya diputuskan dari kecenderungan duniawi,
yakni nafsu makan dan perempuan. Akan tetapi, urung mengingat Nabi Muhammad
sendiri tidak demikian. Dalam perjalanan suluknya, Abû Yazid al-Bistamî menempuh
221 Abdul Ghaffar Chodri, The Mirror of Mohammed (Yogyakarta: Laksana, 2018),
397. 222 Baehaqi Imam, Kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan Dan Reinterpretasi
(Yogyakarta: LKiS, 2000), 27. 223 Yazdi, The Principles of Epistemology in Islamic Phlosophy: Knowledge by
Presence, 35. 224 Sama seperti Abû Yazid al-Bistamî, Hamzah Fansûrî juga mengatakan kemampuan
melayang di udara bukanlah indikator kesufian, tetapi indikator yang baik untuk itu adalah
konsistensinya menjalankan syariat. Lihat, Hamzah Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,” dalam The
Mysticism of Hamzah Fansuri,,,, 268.
59
perjalanan menuju fânâ, lalu menuju baqâ, hingga menyatu (ittihad) dengan Haqq
Ta’ala. Perjalanan ini ditempuh dengan latihan yang keras dalam waktu yang tidak
singkat.
Seorang pesuluk adalah yang sangat taat terhadap syariat. Oleh sebab itu, suatu
waktu Abû Yazid al-Bistamî berhadas dan harus mandi. Dia memutuskan mandi di
tengah cuaca sangat dingin dengan kembali mengenakan jubah yang telah dicuci
dengan salju. Karena tubuhnya tidak sanggup, Abû Yazid al-Bistamî jatuh pingsan.
Begitulah perjuangan seorang sufi untuk syariat. Maka dari itu, akan mengherankan
apabila ada yang menuduh sufi itu ingkar syariat.
Dalam ajaran tasawuf, fânâ adalah hilangnya wujûd diri. Tahapan fana, yaitu
fânâ fî al-af'al (fana dalam perbuatan), fanâ fîî al-sifat (fana dalam sifat atau watak),
fânâ fî al-asmâ (fana dalam penamaan), dan fânâ fî al-dzat (fana dalam zat). Tahapan
fânâ yang ditempuh Abû Yazid al-Bistamî mirip dengan tingkatan penafian Rabi’ah
al-Adawiyah. Abû Yazid al-Bistamî berkata, "Pada tahap pertama, aku zûhûd
terhadap dunia dan segala isinya. Pada tingkatan kedua aku zûhûd terhadap akhirat
dan segala isinya. Pada tingkatan ketiga aku zûhûd terhadap apa saja selain Allah.
Dan pada tingkatan keempat tidak ada yang tinggal bagiku selain Allah." Oleh karena
itu, tidak ada apa pun yang dirasa, didengar, dilihat, kecuali Allah. Tingkatan ini
disebut 'arif bî Allah. Dari kondisi inilah berangkat menuju tingkatan baqâ, yakni
seorang ‘arif hanya menyadari Wujûd Haqq Ta’ala. Wujûd dirinya dan Wujûd Haqq
Ta’ala seperti satu koin dua sisi. Tingkatan ini juga digambarkan seperti besi yang
mencair dalam api. Api dan besi menjadi bersatu. Dalam kondisi seperti inilah
seorang sufi disebut bersatu dengan Haqq Ta’ala225.
Dalam kondisi bersatu dengan Allah, ketika sufi kehilangan wujûd dirinya,
muncul syatahat, seperti yang terjadi pada Abû Yazid al-Bistamî saat sedang salat
subuh berjamaah. “Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Aku,
maka sembahlah Aku, Maha Suci Aku, Maha Suci Aku, alangkah Maha Agungnya
keadaanku. Tidak ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku. Maha Suci Aku,
Maha Suci Aku, Maha Besar Aku." Sontak para jamaah terkejut dan menganggap
Abû Yazid al-Bistamî telah gila226.
Dhu’nûn al-Misrî memang telah merintis kajian filosofis dalam tasawuf. Akan
tetapi, dia tidak mengeluarkan pernyataan kontroversial seperti dilakukan Abû Yazid
al-Bistamî. Pengalaman mistik dalam tasawuf memang sulit menghindari syatahat.
Namun, Junayd al-Baghdadî dapat dikatakan sebagai sufi yang punya pengetahuan
dan amalan tasawuf yang tinggi, tetapi tidak mengemukakan pernyataan-pernyataan
kontroversial227. Junayd al-Baghdadî merupakan guru sufi para penempuh jalan
tasawuf. Tidak hanya untuk tasawuf falsafi, bahkan dia merupakan guru bagi
pengikut tasawuf akhlak. Dalam pandangan Junayd al-Baghdadî, fânâ bukan
merupakan tujuan utama penempuh jalan Ilahi. Setelah status fanâ, penempuh jalan
spiritual mencapai tahap selanjutnya, yakni bâqâ. Lalu, seorang sufi akan turun
225 Kilic, “Mysticism,”.., 947; Bakhsh, Sufisme Islam, 83. 226 Keeler, “Wisdom in Controversy.”,,,, 1-26. 227 Corbin, History of Islamic Philosophy,,,, 192.
60
bersama masyarakat untuk mengajak mereka menempuh jalan spiritual228. Menurut
Junayd al-Baghdadî, tasawuf adalah bahwa engkau bersama Allah tanpa perantara229.
Junayd al-Baghdadî memiliki banyak murid, termasuk yang mempelajari
tasawuf darinya. Adapun murid Junayd al-Baghdadî yang paling terkenal adalah Abû
Mansûr al-Hallaj. Dalam menghadapi syatahat muridnya itu, Junayd al-Baghdadî
telah mengingatkan agar tidak mengabarkan rahasia Haqq Ta’ala kepada masyarakat
umum. Junayd al-Baghdadî sendiri memahami bahwa dalam kondisi fânâ, seorang
sufi menjadi tidak dapat mengendalikan diri230. Junayd al-Baghdadî menyadari
seorang sufi tidak punya niat meresahkan masyarakat umum. Akan tetapi, sebagai
seorang mufti di Irak, dia tidak dapat berbuat banyak. Dia terpaksa memutuskan
tindakan Abû Mansûr al-Hallaj itu melanggar syariat. Dalam putusannya, Junayd al-
Baghdadî mengatakan bahwa secara syari'at, Abû Mansûr al-Hallaj memang
bersalah. Secara hakikat, hanya Allah yang tahu.
Junayd al-Baghdadî adalah sufi yang sangat menekankan pentingnya ibadah.
"Ibadah bagi sufi adalah seperti mahkota di atas kepala raja-raja", kata Junayd al-
Baghdadî. Dia mempraktikkan ibadah yang sangat keras. Setelah mengajar, Junayd
al-Baghdadî salat hingga empat ratus rakaat. Ketika sakit, dia salat sangat banyak
dalam segala kondisi yang memungkinkan. Bila sanggup duduk, dia duduk. Bila
tidak, dia salat dalam keadaan berbaring231. Ketekunan ibadah itu umumnya
diteladani murid-muridnya, termasuk Abû Mansûr al-Hallaj (866–923). Akan tetapi,
muridnya ini mencapai tingkatan sufi yang sangat tinggi. Namun, dia kesulitan, atau
mungkin sengaja, mengutarakan syatâhat sangat kontroversial hingga dieksekusi.
Abû Mansûr al-Hallaj adalah salah satu sufi kontroversial yang paling dikenal232.
Abû Mansûr al-Hallaj mengatakan kekafiran adalah jalan penyatuan dengan
Wujûd Haqq Ta’ala. Menurutnya, agama memang berdaya guna, tetapi hanya
sementara untuk mengenal keimanan. Keimanan dalam agama adalah keimanan
artifisial. Seseorang harus mengingkari keabsahannya, menjadi kafir atas agama
karena konten agama itu artifisial. Seorang saleh harus menempuh jalan spiritual agar
menemukan iman sejati233.
Dalam pengalaman fânâ, Abû Mansûr al-Hallaj mengucapkan kalimat
kontroversial, “Anâ Al-Haqq, akulah Kebenaran Nyata” karena dia tidak dapat lagi
menemukan kediriannya sehingga sebenarnya yang mengucapkan itu adalah Allah234.
Dalam pengalaman itu, yang menyeru dan yang diserukan menjadi tak teridentifikasi.
Sebab itulah, Abû Mansûr al-Hallaj mengatakan bahwa apabila masuk mengakui
eksistensi diri, membedakan diri (aku) dan Dia (Kau), adalah seperti sebuah
228 Muhammad Nur Jabir, Perempuan: Perspektif Tasawuf, (Jakarta: Rumi Press),17. 229 Shams Inati,. dan Elsayed M. H. Omran,, “Al-Junayd on Unification and Its Stages:
A Critical Examination,” Digest of Middle East Studies 3, no. 3 (July 1994): 23–35. 230 Hamka, Tasawuf dari Abad ke Abad (Jakarta: Pustaka Islam, 1962), 94–95. 231 Christopher Melchert, “Origins and Early Sufism,” in The Cambridge Companion
to Sufism, 2014. 232 Corbin, History of Islamic Philosophy…, 197. 233 Carl W. Ernest, Words of Ecstasy in Sufism (New York: State University of New
York Press, 1985), 103. 234 Louis Massignon, Diwan Al-Hallaj, (Yogyakarta, Putra Langit, 2003), 93.
61
keangkuhan yang dipraktikkan Iblis235. Abû Mansûr al-Hallaj menggambarkan
pengalaman mistiknya dengan sebuah pancaran kilau cahaya. Kehadirannya
menyambar seperti guntur. Dia mengatakan, pengalaman ini adalah sebuah kesaksian
yang nyata, bukan kebohongan seperti dilakukan umumnya penganut agama,
mengaku menyaksikan (asyhadu), tetapi sebenarnya tidak melihat-apa-apa236.
Kesaksian demikian hanya sebuah ucapan tanpa makna, tindakan tersebut hanya
sebuah rutinitas semata237.
Sebenarnya, kontroversialisme sufi tidak hanya dilakukan melalui ucapan,
namun juga dalam perbuatan. ‘Ain al-Qudat al-Hamadanî (1098–1131), sebagaimana
dikatakan Hamzah Fansûrî dalam ‘al-Muntahî’, melakukan sebuah praktik
kontroversial dengan menyembah anjing. Hamzah Fansûrî menerangkan, praktik
tersebut dilakukan dengan alasan bahwa ‘Ain al-Qudat al-Hamadanî sudah tidak
dapat lagi mengidentifikasi partikularitas majemuk. Dalam kondisi fânâ, dia hanya
bisa melihat Wujûd Haqq Ta’ala semata238. ‘Ain al-Qudat al-Hamadanî memang
terkenal begitu kontroversial sehingga dieksekusi pada usia yang masih sangat muda.
Dia telah mempelajari dan menekuni karya-karya Abû Hamid al-Ghazalî pada usia
dua puluh satu dan sibuk dengan itu selama empat tahun. Namun, ‘Ain al-Qudat al-
Hamadanî memilih jalan berbeda dengan menganut tasawuf falsafi dan melakukan
uzlah selama dua puluh hari bersama Ahmad Al-Ghazalî, adiknya Abû Hamid al-
Ghazalî 239.
Sama dengan Abû Mansûr al-Hallaj, ‘Ain al-Qudat al-Hamadanî mengatakan
bahwa puncak perjalanan spiritual adalah kekafiran. Penempuh jalan spiritual harus
mengingkari keberadaan dirinya. Salîk harus benar-benar menemukan bahwa wujûd
itu hanya satu, tidak ada identitas wujûd yang nyata, selain Wujûd Haqq Ta’ala. Sama
seperti Abû Mansûr al-Hallaj, ‘Ain al-Qudat al-Hamadanî menegaskan salik supaya
melepaskan diri dari cara beragama masyarakat umum karena cara mereka tidak
memberikan apa pun, kecuali sebatas rutinitas. Berbeda dengan Abû Mansûr al-
Hallaj, ‘Ain al-Qudat al-Hamadanî menolak iktikad hûlûl, yakni Tuhan turun pada
insan pilihan. Menurut Ain al-Qudat al-Hamadanî, iktikad sejati dalam jalan spiritual
adalah meniscayakan wujûd hanya satu sehingga tidak seperti hûlûl yang
meniscayakan adanya dualitas wujûd yang kemudian menyatu. Akan tetapi, para sufi
setelah Ibn ‘Arabî mengatakan bahwa ittihad dan hûlûl hanya istilah yang digunakan
235 Louis Massignon, The Passion of Al-Hallaj: Mystic and Martyr of Islam (Princeton:
Princeton University Press, 1994), 86, 236 Miswari, “Cara Gila Jatuh Cinta: Analisa Qasidah Dan Muqataat Mansur Al-
Hallaj,” Al-Mabhats 4, no. 1 (2019): 51–74. 237 Goenawan Mohamad, Tuhan Dan Hal-Hal Yang Tak Selesai (Yogyakarta: Diva
Press, 2019), 65. 238 Lihat, Al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansûrî , 189. 239 Kautsar Azhari Noer, ed., “Al-Risalah Fi Al-’Ilm Al-Tshawwuf Al-Qusyairi,”
dalam Warisan Agung Tasawuf: Mengenal Karya Besar Para Sufi (Jakarta: Sadra Press,
2015), 240.
62
sufi generasi awal240. Pada masa itu, bahasa yang dimiliki kaum sufi sangat terbatas
sehingga mereka terpaksa menggunakan istilah-istilah yang tersedia. Namun
sebenarnya, kaum sufi generasi awal itu tidak beriktikad demikian. Mereka tidak
berpandangan tentang adanya dualitas yang kemudian, baik itu ittihad sebagaimana
diistilahkan Abû Yazid al-Bistamî maupun konsep hûlûl sebagaimana diistilahkan
Abû Mansûr al-Hallaj241. Keterbatasan bahasa yang dapat digunakan juga berperan
membuat ‘urafâ menggambarkan pengalaman mistiknya dengan istilah-istilah
kontroversial.
Menurut ‘Ain al-Qudat al-Hamadanî, pengetahuan tentang Al-Haqq terbagi
tiga, yaitu mengenai perbuatan, perintah, dan keyakinan. Puasa berarti berpesta
bersama Tuhan. Haji berarti perjalanan menuju hati. Menurut ‘Ain al-Qudat al-
Hamadanî, manusia tidak perlu mendambakan surga karena surga itu adalah tawanan
hati. Bila hati telah bersih, surga itu mudah saja baginya. Sebab itu, hati tidak boleh
ditambatkan pada dunia242.
Konsep-konsep ajaran Wujudiah baru dipahami setelah Ibn ‘Arabî yang
memiliki kedalaman analisis dan penyampaian ajaran melalui sistematika yang kaya.
Ibn ‘Arabî adalah penganut Wujudiah yang ajarannya disampaikan secara lebih
mendalam, menyeluruh, dan sistematis. Wujudiah adalah istilah dalam ajaran tasawuf
falsafi secara keseluruhan, khususnya ajaran wujûd yang dikembangkan Ibn ‘Arabî
dan diteruskan oleh para pengikutnya seperti Sadr al-Dîn al-Qunâwî, Sayyid Haidar
Amûlî, ‘Abd al-Rahman Jamî, Fadhl Allah al-Burhânpûrî, Hamzah Fansûrî, Shams
al-Dîn al-Sumatranî, dan Sayf al-Rizal. Terminologi Wahdat al-Wujûd sebagai istilah
umum Wujudiah menurut Muhammad Nur Jabir diperkenalkan oleh Ibn Taimiyah
dalam mengkritik ajaran Ibn ‘Arabî. Sementara menurut Kautsar Azhari Noer,
terminologi itu kali pertama digunakan oleh Sadr al-Dîn al-Qunâwî ketika mensyarah
ajaran-ajaran Ibn ‘Arabî.
Meskipun Ibn ‘Arabî dan Hamzah Fansûrî tidak menggunakan terminologi
Wahdat al-Wujûd dalam ajaran Wujudiah mereka, tetapi Wahdat al-Wujûd dianggap
sebagai ajaran Ibn ‘Arabî dan yang sejalan dengan pemikiran Wujudiah Hamzah
Fansûrî. Bahkan, ajaran-ajaran yang identik dengan ajaran Ibn ‘Arabȋ sebelum
dirinya, seperti ajaran Ma'ruf Karkhî, ‘Abd Abbas al-Qassab, Khaja ‘Abd Allah al-
Ansarî, ‘Ain al-Qudat al-Hamadanî, Abû Mansûr al-Hallaj, Abû Yazid al-Bistamî,
dan lainnya meski menggunakan konsep-konsep yang berbeda, ajaran-ajaran mereka
tentang wujûd dapat digolongkan sebagai Wahdat al-Wujûd dari segi makna dan
maksud ajarannya243.
240 Seyyed Ahmad Fazeli, “The System of Divine Manifestation in The Ibn ‘Arabian
School of Thought,” Kanz Philosophia : A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism 1,
no. 2 (December 2011): 109. 241 Seyyed Ahmad Fazeli, “Argumentasi Seputar Ineffability (Kualitas Tak
Tertuliskannya Pengalaman Mistis),” Kanz Philosophia : A Journal for Islamic Philosophy
and Mysticism 1, no. 1 (August 2011): 1. 242 Hamid Dabashi, “’Ain Al-Qudhat Hamadani and Intellectual Climate in His
Times,” in History of Islamic Philosophy Vol. I, ed. Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman
(London & New York, 1996), 380. 243 Fenton, “Judaism and Sufism,” 760.
63
Pernyataan Ibn 'Arabî, seperti, “fa ma dhahirû fî al-wujûd bî al-wujûd illâ al-
Haqq, fa al-wujûd huwâ al-Haqq wa huwâ wahid"244, adalah pernyataan yang
menurut William Chittick245 adalah penegasan bahwa wujûd itu hanya satu sehingga
dapat dikatakan sebagai sebuah ajaran Wujudiah246. Ibn ‘Arabî mengatakan bahwa
Wujûd Haqq Ta’ala adalah seluruh urusan dari awal hingga akhir. Segala
keberagaman adalah penampakan dari Wujûd Haqq Ta’ala. Kemajemukan wujûd
realitas yang tampak dalam pandangan Ibn ‘Arabî bukan berarti wujûd itu majemuk.
Kesan kemajemukan itu menunjukkan bahwa Haqq Ta’ala bermanifestasi dalam
beragam bentuk247. William Chittick248 menjelaskan pendapat Ibn ‘Arabî tersebut
dianalogikan dengan cahaya yang menghantam prisma, lalu memunculkan beragam
bentuk dan warna. Keberagaman bentuk dan warna hanyalah keberagaman
manifestasi cahaya. Sementara cahaya itu tetap tunggal.
Ibn ‘Arabî menganalogikan kemajemukan yang tidak mengubah ketunggalan
wujûd sebagai sumbernya sekaligus menjelaskan sistem aktualitas kemajemukan dari
ketunggalan melalui analogi napas dan manusia. Manusia dianalogikan dengan zat,
sementara nafs al-Rahman yang menjadi asal-usul sebagai kemajemukan
dianalogikan dengan napas. Antara zat dengan nafs al-Rahman hubungannya seperti
manusia dengan napasnya. Apabila manusia tidak memiliki napas, tidak disebut
manusia, tetapi mayat. Sementara apabila napas tidak ada manusianya tidak disebut
napas, tetapi udara. Epistemologi Wujudiah dijelaskan melalui konsep wujûd dan
‘adam, Al-Haqq dan khalq, tajallî, zhahir dan bathin, wahdah dan katsrah, tanzih dan
tasybih, Zat dan Nama-nama, al-'ayan al-tsabitah, dan al-insan al-kâmil249.
Dalam konsep epistemologi Wujudiah yang dikembangkan Ibn ‘Arabî, telah
tampak kesempurnaan sebuah sistem epistemologi yang disumbangkan oleh ajaran
filsafat, khususnya filsafat Ibn Sînâ. Sistem ini menginspirasikan Ibn ‘Arabî dalam
membangun sistem Wujudiah menjadi lebih komprehensif dibandingkan sufi
sebelumnya yang memiliki iktikad yang sama, namun belum memiliki kecanggihan
sistem epistemologi.
Misalnya, sebagaimana sistem epistemologi filsafat dipinjam, dimodifikasi,
dan diterapkan Ibn ‘Arabî dalam membahas konsep wujûd dan ‘adam. Ibn ‘Arabî
lebih dahulu menerapkan prinsip identitas dan nonkontradiksi dalam memberikan
batasan antara wujûd dan ‘adam. Bahwasanya wujûd bukan ‘adam dan ‘adam bukan
wujûd. Wujûd oleh Ibn ‘Arabî dibagi kepada tiga pembagian yakni, pertama, Wujud
Hakiki yakni Haqq Ta’ala250. Kedua adalah wujûd yang memiliki wujûd dari
pemberian Wujûd Hakiki, yakni kemajemukan alam. Ketiga adalah sesuatu yang
244 Muhyiddin Ibn'Arabî, Al-Fûtûhât Al-Makkiyah Vol. 2, (Beirut: Dâr al-Shadir, t.t.),
517. 245 Willam C. Chittick, The Self-Disclosure of God: Principles of Ibn Al-’Arabi’s
Cosmology (New York: State University of New York Press, 1997), 22–23. 246 Jabir, Wahdah Al-Wujûd Ibn ‘Arabî dan Filsafat Wujûd Mulla Sadrâ…, 3. 247 Herawati, “Concerning Ibn ’Arabi’s Account of Knowlegde of God (Ma’rifa) Al
Haqq.”, 219. 248 William C. Chittick, Imaginal Worlds: Ibn Al-’Arabi and the Problem of Religious
Diversity (New York: State University of New York Press, 1994), 25. 249 Miswari, Filsafat Terakhir…, 172–177. 250 Muhyiddin Ibn'Arabî, Al-Fûtûhât Al-Makkiyah…, Vol. 2, 475.
64
wujûd sekaligus bukan wujud, dia bersama Wujûd Hakiki sejak asali. Ia itu adalah
materi primer. Pembagian wujud ini bukan pada sisi waktu (kedahuluan dan
kemudian), melainkan dalam urutan logika. Maka dari itu, kategorisasi Ibn ‘Arabî ini
terhindar dari perdebatan teologi Abû Hamid al-Ghazalî dan filsafat Ibn Sînâ251.
Sementara itu, Kautsar Azhari Noer menjelaskan, ‘adam dibagi menjadi
empat, yakni, pertama, ketiadaan mutlak, seperti sekutu Tuhan. Kedua ketiadaan
yang wujudnya mesti secara lebih kuat dan pilihan, seperti differensia dalam genus.
Ketiga adalah ‘adam yang wujudnya mungkin, seperti manisnya air laut. Keempat
adalah ketiadaan yang wujudnya mustahil secara pasti dan pilihan, kecuali wujudnya
differensia tertentu dari sebuah genus252.
Al-Haqq dan khalq adalah sistem yang menjelaskan hubungan antara Haqq
Ta’ala dengan ciptaan. Hubungan ini dianalogikan seperti makanan dan yang
memakan. Makanan itu seperti al-Haqq yang mengisi keseluruhan diri yang
memakan. Tajallî adalah manifestasi Wujûd Haqq Ta’ala kepada makhluk-makhluk.
Tajallî terjadi secara terus-menerus, tidak ada pengulangan, dan tidak sama bagi tiap-
tiap entitas. Tajallî terjadi tergantung pada kesiapan lokus tajallî.
Zhahîr dan bathîn adalah skema untuk menggambarkan hubungan Haqq
dengan khalq. Dalam hal ini, digambarkan sebagai saling meresap, seperti wol yang
meresap air sehingga yang tampak adalah sifat yang diresapi. Demikian pula ketika
Haqq meresap ke dalam khalq, yang tampak adalah sifat Haqq.
Wahdah dan katsrah adalah pernyataan paling jelas yang menunjukkan bahwa
pemikiran Ibn ‘Arabî adalah Wahdat al-Wujûd. Dalam menjelaskan wahdah dan
katsrah, Ibn ‘Arabî menganalogikan kesatuan dan kemajemukan dengan angka.
Berapa pun nominal angka, semuanya adalah berasal dari satu realitas yang nyata,
yakni angka satu. Angka-angka yang banyak itu sebenarnya adalah bentukan
inteleksi. Pada setiap angka berapa pun adalah kehadiran satu. Demikian pula
kemajemukan entitas adalah kehadiran yang satu dan menjadi majemuk karena
proyeksi mental253.
Dalam konsep tanzih dan tasybîh dijelaskan bahwa tanzih adalah menyucikan
Allah dari segala keidentikan apa pun dengan makhluk. Sementara tasybîh berarti
terjadinya manifestasi Haqq Ta’ala dalam bentuk nama dan sifat. Dalam tanzih
terkandung tasybih. Akan tetapi, dalam tasybih tidak terkandung tanzih, seperti dalam
Al-Qur’an terkandung Al-Furqan, tetapi dalam Al-Furqan tidak terkandung Al-
Qur’an. Sebab itulah, dalam pembahasan tentang al-insân al-kâmil, ‘Abd al-Karîm
al-Jîlî mempertegas bahwa nama-nama dan sifat itu sebenarnya adalah perangkatnya
al-insân al-kâmil. Namun, terdapat nama-nama yang dapat diidentikkan dengan
Haqq Ta’ala karena sifat-sifat itu tidak dimiliki khalq, seperti sifat al-Ghanî.
Nama-nama itu adalah kebutuhan makhluk. Nama-nama itu statusnya adalah
berada dalam status mental sehingga tergolong dalam status epistemologis.
Antarnama memiliki berbagai tingkatan dalam tinjauan berbagai aspek. Dalam aspek
kebersyaratan, al-Qadîr membutuhkan al-Murîd, al-Murîd membutuhkan al-‘Alîm,
251 Corbin, Creative Imagination in the Sufism of Ibn Arabi,,,, 200. 252 Kautsar Azhari Ibn ‘Arabi Noer: Wahdat Al-Wujûd Dalam Perdebatan,,,, 45. 253 Miswari, “Filosofi Komunikasi Spiritualitas: Huruf Sebagai Simbol Ontologi dalam
Mistisme Ibn ’Arabî.”
65
dan al-‘Alîm membutuhkan al-Hayy. Dalam aspek kemencakupan, yang terdahulu
mencakup yang terkemudian: Al-Hayy mencakup al-Alîm, Al-Murîd, dan al-Qadîr.
Dalam aspek keterkaitan, al-Qadîr terkait dengan al-Hayy, al-Hayy terkait dengan al-
‘Alîm, dan al-Qadîr terkait dengan al-Murîd254.
Istilah al-’Ayan al-tsabîtah adalah entitas tetap (fixed entity) yang bersifat asali,
terkandung dalam ilmunya Haqq Ta’ala. Posisinya berada antara Haqq dan khalq.
Menjadi baharu dalam aktualitasnya. Segala realitas yang majemuk adalah aktualitas
dari al-‘ayan al-tsabitah255.
Al-insân al-kâmil dalam sistem ajaran Ibn ‘Arabî terbagi ke dalam pembagian
abstrak dan konkret. Secara konkret al-insan al-kâmil adalah para nabi dan sufi. Al-
insân al-kâmil adalah cermin paling bersih sehingga menjadi pemancar (tajallî)
sempurna bagi Nama-nama dan Sifat-sifat al-Haqq256. Al-insân al-kâmil disebut
mikrokosmos (al-‘alam al-saghir) sekaligus makrokosmos (al-‘alam al-kabir)
karena menjadi miniatur bagi alam semesta (mukhtasar al-‘alam). Dalam diri
manusia terhimpun semua kesempurnaan makhluk sehingga al-insân al-kâmil
disebut juga dengan fass (segel) bagi kesempurnaan makhluk257. Al-insân al-kâmil
adalah capaian kesempurnaan yang ditempuh setelah melalui berbagai tahapan.
Tahapan pertama kemanusiaan adalah tahapan awam. Tahapan awam melihat hanya
menggunakan indra dan akal. Dalam tahapan ini, memang diketahui adanya Wujûd
Realitas Tunggal di balik alam materi. Akan tetapi, tidak dapat memahami relasi
Realitas Tunggal dengan alam semesta. Tahapan selanjutnya adalah tingkatan
khawâsh. Khawâsh adalah yang telah mencapai tingkatan kasyaf, melihat kesatuan,
namun ketika kembali tetap saja hanya menemukan kesatuan dan pada kemajemukan
mawjûd dianggap sebagai artifisial saja. Sementara pada tingkatan khawâsh al-
khawâsh, mereka telah mencapai kasyâf, tetapi ketika kembali dalam kemajemukan,
mereka dapat membedakan antara kesatuan dan keberagaman. Analoginya, seperti
melihat cermin, namun mampu membedakan cermin dengan bayangannya258.
Kenikmatan capaian sufi tersebut adalah bagian dari Kasih Sayang al-Haqq. Hal ini
karena Dia adalah realitas yang tersembunyi, namun rindu untuk dikenal. Kerinduan
ini melimpah sebagai Kasih Sayang yang bermanifestasi. Limpahan emanasi (fayd)
terjadi dalam berbagai tingkatan martabat dalam hierarki wujûd. Setiap tingkatan itu
tidak terpisah, tetapi satu kesatuan tunggal. Martabat-martabat itu terbagi dalam
martabat Ilahiyah dan martabat selain Allah (ma siwa Allah).
Martabat Ilahiyah tertinggi adalah Dzat al-Wujûd (ghayb al-ghuyûb).
Martabat ini sama sekali tidak dapat diidentifikasi259. Selanjutnya, dari Dzat al-Wujûd
terjadi ta’ayyûn awwal yang disebut sebagai martabat Ahadiyyah. Martabat ini sudah
254 Penjelasan lengkap, lihat, Noer, Ibn ‘Arabi: Wahdat Al-Wujûd Dalam
Perdebatan,,,, 69–71. 255 Izutsu, Sufism and Taoism: A Comparative Study of Key Philosophical Concepts,,,,
59. 256 Rusdiana, “Pemikiran Ahmad Tafsir Tentang Manajemen Pembentuk Insan
Kamil,” At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam (2017), 97. 257 Chittick, Imaginal Worlds: Ibn Al-’Arabi and the Problem of Religious Diversity…,
23. 258 Corbin, Creative Imagination in the Sufism of Ibn Arabi…, 271. 259 Corbin, Creative Imagination in the Sufism of Ibn Arabi…,195.
66
dapat diidentifikasi dengan atribut negasi, seperti "laisâ kâ mîtslîhî syai’in”.
Selanjutnya, terjadilah ta'ayyûn tsanî yang disebut martabat wahidiyyah. Meskipun
tunggal, dalam martabat ini sudah mengandung keberagaman karena dalam status ini
sudah terkandung Nama-nama dan Sifat-sifat. Di dalam wahidiyyah, sudah
terkandung al-'ayan al-tsabitah sebagai potensi munculnya keberagaman260.
Dalam alam Wahidiyyah memancar tingkatan alam selain ma sîwâ Allah, yakni
munculnya alam jabarût yang merupakan alam rohani murni. Lalu, muncul alam
mitsal yang merupakan alam rohani. Alam ini disebut juga alam imajinal yang
mampu dicapai sufi. Dalam tingkatan ini sufi dapat melihat gambar-gambar masa
depan. Alam mitsal adalah perantara (barzakh) antara alam ruhani (jabârut) dan mulk
(alam indrawi). Mimpi dan alam setelah kematian disebut juga dengan barzakh
karena padanya muncul gambar-gambar261.
Semua tingkatan itu disebut hadrat ilahiyah. Disebut juga al-hâdrâh al-
khamsah karena terdapat lima tingkatan alam yang terbagi kepada alam jabârut, alam
malakût, dan al-insân al-kâmil yang meliputi seluruh tingkatan tersebut. Disebut juga
martabat tujuh (al-martabat al-sab'ah) yang mencakup martabat Ahadiyyah, martabat
wahidiyyah, martabat wahdah (nûr muhammadiyyah), yang mana antara martabat
ahadiyyah dan martabat wahidiyyah ditambah martabat ketiga alam (malakut,
jabârut, dan ajsam, serta al-insan al-kâmil).
‘Ayan al-tsabîtah adalah entitas tetap yang berasal dari ilmu Haqq Ta’ala
(hadrah ilmiyyah) sehingga ia tidak berubah sejak asali dan akan tetap demikian
selamanya. Ia disebut tidak pernah mencium aroma wujûd, yakni keberagaman
karena ia hanya sebagai sumber mawjûdat. Melalui ‘ayan al-tsabîtah terjadilah
keberagaman yang terjadi secara terus-menerus menurut kadar Ilahi262. Dalam
kejadian kemajemukan terjadi alur bolak-balik dari manifestasi kepada alam dan
transendensi Ilahi melalui manusia yang merupakan kesempurnaan alam karena
manusia menghimpun seluruh aspek Ilahiah. Sementara makhluk lain, seperti mineral
hanya mampu menampung aspek kemahakuasaan, nabati selain mampu menampung
aspek kemahakuasaan, juga mampu menampung aspek kehidupan, dan selanjutnya
hingga manusia yang mencakup seluruh aspek Ilahi263.
Barzakh merupakan perantara antara Wujûd Mutlak dengan ketiadaan mutlak.
Prosesnya sebagaimana dijelaskan Ibn ‘Arabî adalah, munculnya barzakh adalah dari
sebuah titik dari Wujûd Mutlak, lalu makin membesar hingga alam materi sehingga
bentuknya seperti terompet tanduk264. Oleh karena itu, ketika nantinya terompet
sangkakala ditiupkan, manusia kehilangan seluruh kesadarannya. Lalu, ketika
ditiupkan lagi, kembalilah kesadaran manusia sehingga dia bangkit dengan kesadaran
260 Seyyed Ahmad Fazeli,, Mazhab Ibn Arabi: Mengurai Paradoksalitas Tasybih dan
Tanzih, Translated. (Jakarta: Sadra Press, 2016), 174–175. 261 Corbin, Creative Imagination in the Sufism of Ibn Arabi…, 205. 262 Narasi "Tidak pernah menciuan aroma wujûd", berangkat dari narasi filsafat yang
menyatakan mâhiyah tidak pernah mencium aroma wujûd . 263 Bagir, Semesta Cinta…, 207–208. 264 Bagir, Semesta Cinta…, 209 Dalam bahasa Arab, terompet disebut dengan shûr
yang berarti gambar. Hamzah Fansûrî menyatakan bahwa alam barzakh adalah shûrah
ilmiyah, yakni alam gambaran ilmu Tuhan.
67
yang lebih tinggi sehingga kesadaran sebelumnya dianggap sebagai kesadaran
gambar dalam tidur (mimpi). Hal ini sesuai dengan sebuah hadis yang menyatakan
bahwa manusia itu dalam kehidupan dunia ini sedang tidur265.
Barzakh adalah konsekuensi dari ambiguitas Huwâ lâ Huwâ (Dia tetapi bukan
Dia). Pada satu sisi, alam adalah dia sekaligus pada saat yang sama bukan Dia. Pada
saat yang sama, alam semesta memiliki sifat rohani sekaligus pada saat yang sama
alam semesta adalah alam materi. Alam semesta memiliki tingkatan wujud masing-
masing. Setiap tingkatan wujûd memiliki barzakh (perantara). Dengan perantara ini
perbedaan muncul pada setiap tingkatan wujûd, sekaligus dengan barzakh
menunjukkan kesatuan dari setiap tingkatan wujûd. Inilah yang menunjang
penyimpulan bahwa pemikiran Ibn ‘Arabî adalah Wahdat al-Wujûd atau Wujudiah266.
Sementara itu, dalam skema alam khayal (alam imajinal) yang mana adalah
tasawuf dipandang sebagai alam yang lebih nyata daripada alam materi, merupakan
alam yang dilihat sufi dalam pengalaman hudhûrî. Alam ini ditangkap melalui,
berbeda dengan filsafat yang bersifat logis-analitik, sistem sintetik-holistik. Oleh
karena itu, umumnya sufi lebih suka mengekspresikan (mengomunikasikan) melalui
puisi, ketimbang analisis deskriptif267.
Haidar Bagir268 berpendapat tiga tingkatan pengetahuan tasawuf. Pertama
adalah pengalaman sang sufi sendiri yang bersifat rohani. Pengalaman ini murni
spiritual sehingga tak terperi (inafiblity). Selanjutnya adalah ekspresi sufi atas
pengalaman mereka dalam sebuah bentuk komunikasi, seperti puisi atau prosa.
Tingkatan ini disebut dengan ‘irfan misalnya, mengatakan Ibn ‘Arabî adalah
representasi terbaik. Tingkatan ketiga adalah analisis filosofis-deskriptif atas
Wujudiah sebagaimana dilakukan oleh Henry Corbin, William Chittick269, Toshihiko
Isutzu270, dan Kautsar Azhari Noer atas ‘irfan Ibn ‘Arabî; analisis Louis Massignon271
atas ‘irfan Abû Mansûr al-Hallaj; analisis Drewes dan Brakel272, Doorebos273, Syed
Muhammad Naquib Al-Attas274, Abdul Hadi WM275 atas Wujudiah Hamzah Fansûrî
, dan analisis Abdul Aziz Dahlan atas ‘irfan Shams al-Dîn al-Sumatranî276. Kajian-
265 Izutsu, Sufism and Taoism…, 7–8. 266 Bagir, Semesta Cinta,,,, 210. 267 Abdul Hadi W.M. menjelaskan dengan baik signifikansi puisi sebagai sarana
komunikasi metafisika dengan alam materi, lihat, Abdul Hadi WM, Hermeneutika, Estetika,
dan Religiusitas: Esai-Esai Sastra Sufistik dan Seni Rupa…, 126–127. 268 Bagir, Semesta Cinta…, 236. 269 Chittick, The Self-Disclosure of God: Principles of Ibn Al-’Arabi’s Cosmology, 13. 270 Izutsu, Sufism and Taoism: A Comparative Study of Key Philosophical Concepts,
18. 271 Louis Massignon, The Passion of Al-Hallaj: Mystic and Martyr of Islam, 20-23. 272 Drewes dan Brakel, The Poems of Ḥamzah Fansûrî, 18-20. 273 Johan Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri (Leiden: Betteljee &
Terpstra, 1933), 1-3. 274 Al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansûrî…, 205 . 275 Hadi, Tasawuf Yang Tertindas: Kajian Hermeunetik Terhadap Karya Hamzah
Fansûrî, 243. 276 Abdul Aziz Dahlan, Penilaian Teologis Atas Paham Wahdatul Wujud Dalam
Tasawuf Syamsuddin Sumatrani (Padang: IAIN Imam Bonjol Press, 1992), 12.
68
kajian tersebut disebut juga filsafat tasawuf. Kesempurnaan ajaran Wujudiah
menginspirasi dan memudahkan para sufi setelahnya dalam mengkaji dan
mengembangkan ajaran tersebut. Sufi, seperti Hamzah Fansûrî menerjemahkan
ajaran tersebut dalam nuansa Melayu-Nusantara. Ajaran Hamzah Fansûrî
mendapatkan penentangan hebat dari Nûr al-Dîn al-Ranîrî.
C. Pandangan atas Teori Wujûd dalam Filsafat dan Wujudiah
Tradisi diskursus wujûd atau diskursus yang sepadan dengannya telah
dimulai sejak filsafat Yunani. Diskursus ini dianalisis secara lebih mendalam dan
serius dalam filsafat Islam. Dalam diskursusnya, filsafat Islam menjadi berbeda
dengan filsafat Yunani karena memuat porsi kajian Ilahiah yang sangat luas dan
mendalam. Keunikan ini terbentuk dengan mengelaborasi filsafat Neoplatonisme
yang dipandang mengandung kajian metafisika yang lebih luas dibandingkan ajaran
Aristoteles.
Sebagai filsuf pertama dalam dunia Islam, al-Kindî memulai diskursus kajian
wujûd dengan memperbanyak kajian ketuhanan dalam filsafat. Kajian-kajiannya itu
mengelaborasikan kajian metafisika Aristoteles dan Neoplatonisme. Selanjutnya, al-
Fârâbî menelisik diskursus wujûd yang dibedakan dengan mâhiyah. Al-Fârâbî
merumuskan konsep emanasi Neoplatonisme sebagai kajian proses manifestasi
wujûd secara lebih sistematis. Manifestasi wujûd sebagai daya jiwa juga mulai
dirumuskan oleh Al-Fârâbî. Dia juga menggambarkan manifestasi wujûd ke dalam
empat kategori inteleksi (‘aql).
Kemudian, Ibn Sînâ meneruskan fokus perbedaan wujûd dan mâhiyah
dengan menginvestigasi manakah antara keduanya yang fundamental (asil)? Jawaban
dari pertanyaan ini sangat penting karena hanya yang fundamental itulah yang nyata
dan memiliki realitas. Sementara yang tidak fundamental, yakni ‘itbar hanya
merupakan bentukan pikiran. Dalam hal ini, Ibn Sînâ berpandangan bahwa wujûd
yang fundamental dan dan mâhiyah hanya suatu ‘itibar.
Ibn Sînâ membagi wujud kepada beberapa pembahasan, yakni Wajîb al-
Wujūd, mumkin al-wujūd, dan mumtanî al-wujūd. Wajîb al-Wujūd terbagi kepada
Wajîb al-Wujûd lî nafsihî yang merupakan sumber wujud dan wajîb al-wujûd lî
ghayrihî, yakni mumkin al-wujūd yang aktual akibat pemberian wujûd oleh Wajîb al-
Wujûd lî nafsihî. Dalam pandangan Ibn Sînâ, aspek tertentu dari aksiden Wajîb al-
wujûd lî ghayrihî terlibat dalam hukum gerak karena bukan merupakan wujud yang
sempurna277.
Syihab al-Dîn al-Suhrawardî yang datang kemudian membangun aliran filsafat
al-Hikmah al-Isyrâqiyyah. Dia menyanggah gagasan Ibn Sînâ dengan berpandangan
bahwa yang mendasar itu adalah mâhiyah sementara wujûd hanyalah proyeksi
pikiran. Dia mengajukan pandangan bahwa wujûd hanya menjadi tambahan bagi
mâhiyah. Menurut Syihab al-Dîn al-Suhrawardî mâhiyah yang menjadi dasar realitas
adalah cahaya yakni Nûr al-Anwâr. Cahaya utama ini beriluminasi pada cahaya yang
mengendalikan (al-anwâr al-qahirah) dan cahaya yang mengatur (al-anwâr al-
mudabbirah)278. Kritik Syihab al-Dîn al-Suhrawardî kepada Ibn Sînâ tentang mana
277 Hanafi, Filsafat Islam…, 131–132. 278 Ziai, Suhrawardi dan Filsafat Illuminasi…, 225–227.
69
yang mendasar antara wujûd dan mâhiyah terjadi karena ketidakjelasan Ibn Sînâ
dalam mengeklaim kemendasaran wujûd atas mâhiyah apakah terjadi pada konsepsi
pikiran atau ada realitas. Syihab al-Dîn al-Suhrawardî mengira, Ibn Sînâ menegaskan
wujûd kemendasaran mâhiyah adalah pada ranah konseptual. Namun ternyata,
maksud Ibn Sînâ wujûd mendasar atas mâhiyah adalah pada realitas eksternal.
Kemudian, Mullâ Sadrâ membela Ibn Sînâ dengan menjelaskan berbagai argumentasi
kemendasaran wujûd atas mâhiyah.
Dalam diskursus Wujudiah, fokus pembahasannya adalah Wujûd Haqq Ta’ala.
Kaum sufi falsafi tidak hanya berfokus pada ritual dalam tarekat dan penyucian jiwa
dalam tindak sehari-hari, seperti mempraktikkan sikap wâra', qana’ah, dan zûhûd,
tetapi juga memberikan perhatian serius dalam kajian filosofis terhadap Wujûd Haqq
Ta’ala. Sebab itulah, dalam Wujudiah, lahir berbagai konsep dan teori tentang
pemahaman atas Wujûd Haqq Ta’ala. Konsep-konsep yang mereka lahirkan
memunculkan banyak polemik dan utamanya ditentang oleh mutakallimîn dan
fuqâhâ. Demikian juga dalam praktik keagamaan, banyak tindakan dan ucapan
mereka dianggap kontroversial279.
Para sufi Wujudiah menegaskan ajaran mereka adalah tauhid yang lurus.
Sekalipun landasan epistemologis ajarannya berdasarkan dari pengalaman spiritual,
tetapi mereka mengeklaim pengalaman-pengalaman itu sesuai dengan doktrin Al-
Qur’an sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an 2 (Al-Baqarah): 115, Al-Qur’an 2
(Al-Baqarah): 186, Al-Qur’an 4 (al-Nisa’): 126, Al-Qur’an 8 (al-Anfāl): 17, Al-
Qur’an 28 (al-Qisash): 88, Al-Qur’an 50 (Qāf): 16, Al-Qur’an 57 (al-Hadîd): 3; Al-
Qur’an 58 (al-Mujādilah): 7. Namun, hal yang membuat pandangan sufi Wujudiah
menjadi makin kontroversial adalah penafsiran mereka secara esoteris atas ayat-ayat
Al-Qur’an sehingga di tangan mereka, pemahaman mereka terhadap Al-Qur’an
menjadi berbeda dengan mutakallimîn, fuqâhâ, dan masyarakat umum.
Perjalanan spiritual kaum sufi falsafi adalah berusaha mencapai fânâ, yakni
meleburnya wujûd diri ke dalam Wujûd Haqq Ta’ala. Dalam usaha ini, wujûd
manusia berangkat dari jiwa rendah (al-nafs al-ammârah), lalu berproses dalam jiwa
terilhami (al-nafs al-mulhamah), jiwa damai (al-nafs al-muthmainnah), jiwa tulus
(al-nafs al-radhiyyah), jiwa yang diridhai (al-nafs al-ardhiyyah), untuk mencapai
jiwa sempurna (al-nafs al-kâmilah). Status fânâ berproses dari fânâ fî al-asmâ
menuju fânâ fî al-dzat.
Rabi’ah al-Adawiyah dan Sufyân al-Tsaurî adalah sufi generasi awal yang
mengajarkan tasawuf secara ketat. Namun, Dhu’nûn al-Misrî memulai diskursus
kajian wujûd menjadi sangat filosofis. Usaha ini dilanjutkan Abû Yazid al-Bistamî
yang merumuskan gagasan tentang kemenyatuan (ittihad) wujûd diri ke dalam Wujûd
Haqq Ta’ala. Manusia harus melepaskan alam kemanusiaannya (nasût) menuju alam
Ilahi (lâhût) atau aspek kemanusiaan. Sementara aspek wujûd rohani disebut dengan
lâhût atau aspek ketuhanan. Sementara Abû Mansûr al-Hallaj merumuskan gagasan
tentang Wujûd Haqq Ta’ala bermanifestasi (hûlûl) ke dalam wujûd manusia sehingga
wujûd manusia melebur dalam Wujûd Haqq Ta’ala.
279 Kilic, “Mysticism,” in History of Islamic Philosophy Vol. II…, 947.
70
Konsep-konsep wujûd yang dibangun para sufi, seperti Abû Yazid al-Bistamî
dan Abû Mansûr al-Hallaj oleh sufi setelahnya dianggap belum mencapai kesatuan
wujûd (Wahdat al-Wujûd) karena gagasan ittihad dan hûlûl masih mengesankan
adanya dualitas wujûd. Namun, sebenarnya konsep-konsep itu bukanlah pengalaman
yang masih meniscayakan dualitas wujûd, melainkan karena terbatasnya bahasa
filosofis yang mereka miliki. Kesempurnaan konsep wujud dalam Wujudiah barulah
muncul oleh rumusan Ibn ‘Arabî yang telah menyerap banyak bahasa filosofis dari
filsafat sehingga mampu merumuskan konsep-konsep canggih dalam Wujudiah,
seperti wujûd dan ‘adam, Al-Haqq dan khalq, tajallî, zhahir dan bathin, wahdah dan
katsrah, tanzih dan tasybih, Zat dan Nama-nama, al-'ayan al-tsabitah, dan al-insan
al-kâmil280.
Dalam hal ini, Hamzah Fansûrî dan Mulla Sadrâ memperoleh banyak
keuntungan karena konsep wujûd dalam filsafat Islam dan Wujudiah telah mengalami
perkembangan sehingga mereka dapat merumuskan gagasan wujûd dalam perspektif
masing-masing secara lebih matang. Dalam hal ini, Hamzah Fansûrî melakukan
sintesis dan pengejawantahan konsep wujûd dalam Wujudiah dalam konteks yang
mudah dipahami masyarakat Melayu melalui bahasa puitis dan analogi-analogi yang
mudah dipahami masyarakat. Sementara Mulla Sadrâ melakukan sintesis dan kritik
mendalam atas filsafat wujûd dan membangun sebuah gagasan mandiri dalam al-
Hikmah al-Muta’alliyah.
280 Miswari, Filsafat Terakhir…, 172–177.
71
BAB III
KONSEP WUJUDIAH HAMZAH FANSÛRÎ
Mendalami konteks kehidupan dan karier Hamzah Fansûrî menjadi penting
ketika ingin memahami peta pemikirannya. Pada sekitar abad ke-16, karier Hamzah
Fansûrî di negeri Melayu tentu kondisi sosialnya berbeda dengan hari ini sehingga
analogi-analogi yang digunakan Hamzah Fansûrî dalam menjelaskan ajarannya tentu
harus dilihat dalam konteks ruang dan waktu kehidupan Hamzah Fansûrî sendiri dan
lingkungannya.
Hamzah Fansûrî mendapatkan keuntungan, antara lain, karena teori dan konsep
Wujudiah telah disempurnakan oleh Ibn ‘Arabî. Namun, Hamzah Fansûrî
mengemban tugas besar, yakni berusaha mereformulasi ajaran Wujudiah yang rumit
dan berat supaya dipahami oleh masyarakat Melayu. Sebenarnya, ajaran Wujudiah
dapat lebih mudah dipahami apabila sebuah masyarakat akrab dengan tradisi filsafat
karena sebagaimana dirumuskan Ibn ‘Arabî, Wujudiah dijelaskan dengan bahasa dan
sistem yang sangat filosofis.
Masyarakat Kepulauan Indonesia sendiri kurang akrab dengan tradisi filsafat
Islam kecuali terbatas pada penguasaan ilmu mantik sehingga Wujudiah dengan
pendekatan Ibn ‘Arabî menjadi sulit sekali untuk diterima. Dalam hal ini, dengan
bekal pemahamannya yang sangat mendalam atas ajaran Wujudiah dan kepekaan atas
kondisi sosiokultural masyarakat Melayu pada masanya, Hamzah Fansûrî
menghadirkan ajaran Wujudiah dengan menggunakan analogi-analogi dari objek-
objek yang dekat dan mudah dipahami oleh masyarakat. Di antara gagasan penting pemikiran Hamzah Fansûrî adalah penjelasan
tentang tujuh sifat Haqq Ta’âlâ, yakni Hayat, Ilmû, Iradat, Qudrat, Kalam, Samî',
dan Basar. Haqq Ta’âlâ itu Qayyim. Penjelasan tersebut terkandung dalam Asrâr.
Penjelasan-penjelasannya, antara lain, menggunakan berbagai analogi, seperti tanah
dan perabotan, kayu dan buah catur, cahaya dan sinarnya, laut dan ombak, buah
bundar, biji dan kandungan potensinya, cermin dan bayangannya, manusia dan
atributnya, sungai dan alirannya, air dan sifatnya, batu dan kepasifannya, besi dan
tukang besi, dan lainnya.
Bagian ini mengulas tentang kehidupan serta karya-karya Hamzah Fansûrî.
Kemudian, mengulas prinsip dasar ajarannya. Lalu, mengulas analogi-analogi yang
digunakan Hamzah Fansûrî dalam Asrâr dalam rangka menyederhanakan ajaran
Wujudiah agar mudah dipahami masyarakatnya. Terakhir, dilakukan pemaknaan atas
ajaran Wujudiah Hamzah Fansûrî dan analogi-analogi yang digunakan dalam Asrâr.
A. Kehidupan dan Karya Hamzah Fansûrî
Syed Muhammad Naquib Al-Attas mengatakan Hamzah Fansûrî berkarier di
Fansur pada masa kekuasaan Sultan Alauddin Ri’ayat Shah yang memimpin antara
1588–1604. Namun, hasil penelitian itu menjadi perlu dipertanyakan kembali apabila
menerima laporan Kersten281 yang bersandar pada temuan Guillot dan Kalus
sebagaimana dipresentasikan pada Jurnal Archipel yang menyatakan Hamzah
281 Kersten, A History of Islam In Indonesia, 45–50.
72
Fansûrî meninggal pada 1 April 1527282. Pandangan Drewes dan Brakel283 yang
mengatakan Hamzah Fansûrî telah mangkat sebelum 1590 memang benar. A.H. John
juga mengatakan Hamzah Fansûrî telah meninggal sebelum 1600, bahkan sebelum
1590284. Akan tetapi, selisih dugaannya terlalu jauh. Data-data terbaru itu makin
menguatkan pandangan Abdul Hadi WM285 yang membuka peluang besar bahwa
pada masa Sultan Iskandar Muda (1609–1636)286, Hamzah Fansûrî telah lama
mangkat sebelum itu karena pada masa tersebut, mudah saja ajaran martabat tujuh
yang diajarkan Shams al-Dîn al-Sumatranî287 disebarkan karena pengaruh ajaran
Hamzah Fansûrî yang mengajarkan martabat lima telah lama pudar, yaitu sudah
mencapai sekitar satu abad288.
Sementara kritik atas tindakan mafia perdagangan di Bandar Kesultanan Aceh
Darussalam yang melibatkan intrik kotor dalam perpolitikan Kesultanan Aceh
Darussalam, sebagaimana dilaporkan Lombard289, dilancarkan dengan keras oleh
Hamzah Fansûrî:
Berahimu da’im akan orang kaya
Manakan dapat tiada berbahaya
Praktik ini telah menjadi tradisi di Kesultanan Aceh Darussalam sebagaimana
direkam Hamzah Fansûrî. Persaingan dagang yang sengit yang secara langsung
berdampak pada intrik politik. Sementara dengan mudah Hamzah Fansûrî merekam
fenomena tersebut dalam bentuk kritik tentunya menjadi sulit kalau lokasi transaksi
perdagangan yang padat dan diskursus politik yang sengit terjadi di kawasan yang
jauh dengan Istana Dâr al-Dunyâ di Kutaraja290. Amirul Hadi mengatakan, Hamzah
Fansûrî berkarier dan menyebarkan ajarannya dari tempat yang tidak jauh dari pusat
kekuasaan291. Oleh sebab itu, tentulah Fansur dan Hamzah Fansûrî itu tidak berada
jauh dari pusat kerajaan. Dengan demikian, Fansur merupakan pusat transaksi
perdagangan yang padat menjadi mungkin292.
282 Guillot dan Claude Ludvik Kalus, “La Stèle Funéraire de Hamzah Fansûrî,”
Archipel 60, no. 4 (2000): 3–24. 283 Drewes and Brakel, The Poems of Ḥamzah Fansûrî, 3. 284 Johns, “The Poems of Hamzah Fansûrî,” 325. 285 Abdul Hadi WM, Tasawuf Yang Tertindas….., 118–119. 286 Lombard, Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda, (1607-1636), (Jakarta:
Gramedia, 2014), 105. 287 Arifin, “Tuhfah Al-Mursalah: Studi Terhadap Pemikiran Martabat Tujuh Al-
Burhanpury.”, 41-52. 288 M. Afif Ansori, Tasawuf Falsafi Syaikh Hamzah Fansûrî (Yogyakarta: Gelombang
Pasang, 2004), 108–111. 289 Lombard, Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636), 226–227. 290 Amirul Hadi, “The Ṭāj Al-Salāṭīn and Acehnese History,” Al-Jami’ah: Journal of
Islamic Studies 42, no. 2 (2004): 258–293. 291 Amirul Hadi, Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi (Jakarta: Obor, 2010), 89. 292 Azhari, Kapur Dari Barus: Islam Dan Jaringan Perdagangan Kuno, 1–12.
73
Bila merujuk data terbaru yang disebutkan Kersten293, Hamzah Fansûrî lahir
sekitar pertengahan abad ke-15 pada periode akhir Samudra Pasai294. Hamzah Fansûrî
bertolak ke Timur Tengah. Kebesaran Hamzah Fansûrî tentu saja dibutuhkan oleh
Kesultanan Aceh Darussalam yang membutuhkan ulama besar sehingga Hamzah
Fansûrî melanjutkan berkarier di Fansur yang merupakan wilayah Aceh Darussalam
sepulangnya dari pengembaraan295. Pada kondisi itulah, relevansi kontektualisasi
analogi-analogi yang digunakan Hamzah Fansûrî dalam menyebarkan ajarannya.
Wujudiah dianggap sebagai ajaran yang rumit. Namun, Hamzah Fansûrî
mengkontekstualisasikan ajaran tersebut dengan kondisi lingkungan dan
sosiokultural Fansur, dunia Melayu, pada masa ia berkarier.296
Hamzah Fansûrî adalah sufi Melayu pengajar Wujudiah yang telah
menghasilkan karya besar dalam tasawuf dan berkontribusi besar dalam
pembangunan sastra Melayu. Karya-karya Hamzah Fansûrî ditulis dalam bentuk
syair dan prosa. Syair-syair yang telah diperjelas dapat ditemukan dalam Tasawuf
yang Tertindas karya Abdul Hadi WM dan The Poems of Hamzah Fansûrî karya
Drewes dan Braker. Drewes dan Braker mengulas syair-syair Hamzah Fansûrî dari
manuskrip-manuskrip yang tersedia di Eropa. Abdul Hadi WM mengulas syair-syair
sufi besar itu dari manuskrip yang tersimpan di Jakarta297. Namun, syair-syair yang
berhasil dianalisis Abdul Hadi WM tampak lebih lengkap. Terdapat total sekitar tiga
puluh puisi. Sementara itu, terdapat tiga karya prosa Hamzah Fansûrî yaitu Asrâr,
Syarâb, dan al-Muntahî yang telah ditransliterasi dengan baik oleh Syed Muhammad
Naquib Al-Attas.
Adapun secara umum, pesan-pesan Hamzah Fansûrî dari sekitar tiga puluh
puisinya adalah penjelasan tentang Hakikat Haqq Ta’ala, kondisi alam spiritual,
status manusia dan alam sebagai wujûd yang bergantung secara mutlak kepada Haqq
Ta’ala, dan pesan peringatan kepada manusia untuk mempersiapkan bekal kembali
kepada Allah. Sementara prosa Asrâr merupakan penjelasan filosofis tentang puisi
ruba’i-nya yang ditakwikan oleh Hamzah Fansûrî sendiri. Adapun Syarâb
merupakan penjelasan makna batin dari syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Dan
al-Muntahî adalah penguatan argumentasi Wujudiah dengan mengutip Al-Qur’an,
hadis qudsi, hadis, ungkapan para sahabat nabi, dan para sufi.
293 Kersten, A History of Islam In Indonesia, 45–50. 294 Bandingkan dengan Braginsky yang memperkirakan Hamzah Fansûrî lahir sekitar
abad ke-16 atau abad ke-17. Lihat, Vladimir Braginsky, “Towards the Biography of Hamzah
Fansûrî. When Did Hamzah Live ? Data From His Poems and Early European Accounts,”
Archipel 57, no. 2 (1999): 136. 295 Syarif Hidayatullah dan Hamzah Fansûrî sebagai ilmuan besarhampur dapat
dipastikan adalah alumni perguruan terbaik masa itu yakni Dayah Blang Pria di Pasai.
Bandingkan, Aceh Sepanjang Abad Vol. I, 187–196 Mengenai Dayah Blang Pria, lihat,
Saifullah, Pembaruan Pendidikan Islam Di Aceh (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 67–68
lihat juga; Hasjmy, Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh, 57–58. 296 Said, Aceh Sepanjang Abad Vol. I…, 189–196. 297 Syair-syair ditransliterasi hingga mudah dibaca. Hadi W.M.,Abdul, Tasawuf Yang
Tertindas: Kajian Hermeunetik Terhadap Karya Hamzah Fansûrî, 351–441.
74
Puisi-puisi Hamzah Fansûrî antara lain membahas tentang tema ketuhanan
dan hubungannya dengan makhluk298. Ajaran kepada manusia untuk selalu berada di
jalan Allah sangat sarat dalam puisi-puisi Hamzah Fansûrî. Dalam puisinya, Hamzah
Fansûrî mengajarkan supaya manusia tidak terjebak oleh kenikmatan duniawi agar
dapat bersatu (wasil) dengan Allah. Manusia dianjurkan untuk menjadikan ilmu
dimiliki untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk menyombongkan diri.
Prosa Hamzah Fansûrî berjudul Syarâb mengulas tentang makna batin dari
syariat, tarekat, dan makrifat. Prosa berjudul Asrâr adalah penjelasan atas salah satu
puisinya yang mengulas tentang tujuh sifat utama Tuhan dengan menggunakan
berbagai analogi. Prosa berjudul al-Muntahî mengemukakan pandangan-pandangan
penting dari para sufi sebelumnya.
Dalam syair-syairnya, Hamzah Fansûrî mengulas tentang berbagai tema,
terutama tentang berhati-hati terhadap kecenderungan duniawi sebagai jalan menuju
bersatu dengan Allah, membahas tentang gagasan metafisika Hamzah Fansûrî, dan
berbagai tema lainnya, seperti konsep hubungan antara ketunggalan dan
kemajemukan. Dalam pandangan Hamzah Fansûrî, jalan menuju wasil (bersatu)
dengan Allah adalah dengan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Potensi lahiriah
dan batiniah harus dikerahkan dengan usaha keras. Manusia harus menyadari dirinya
seperti dagang, datang sejenak lalu segera pergi. Manusia harus selalu berbaik sangka
karena mereka hanya mampu mengenal sesuai secara terbatas karena sejatinya
segalanya adalah keindahan:
Rumahnya alî berpandam birai
Lakunya bijak sempurna bisai
Tudungnya halus terlalu pingai
Da'im berbunyi di balik tirai
Langkah pertama menuju keberuntungan adalah menemukan guru yang tepat
(mursyîd). Selanjutnya, harus melatih mengendalikan hawa nafsu. Hamzah Fansûrî
berkata:
Rantaikan hendak sekalian musuh
Anjing tunggal yogya kau bunuh
Dengan mahbubmu seperti suluh
Supaya dapat berdekap tubuh
Pada puisi ketiga dalam susunan oleh Abdul Hadi WM, Hamzah Fansûrî
mengatakan bahwa Allah adalah Wajîb al-Wujûd. Wujûd Allah adalah al-Awwal dan
Dia pula al-Akhîr. Allah adalah Cahaya sekaligus Sumber cahaya (Nûr 'Ayn). Cahaya
adalah asal dari semua makhluk. Awalnya, cahaya ini berada dalam pengetahuan
Allah, lalu memancar menjadi sekalian alam.
Awwal dan akhir asmanya jarak
Lahir dan batin rupanya banyak
298 Kautsar Azhari Noer, Ibn ‘Arabî: Wahdat al-Wujûd dalam Perdebatan, hal. 74
75
Sengguhpun dua ibu dan anak
Keduanya cahaya dari sana nyarak
Hamzah Fansûrî sendiri menggambarkan hakikat kemajemukan seperti kain
dan kapas299. Sekalipun namanya berbeda, hakikatnya hanya satu. Pemahaman itu
hanya dapat dialami sendiri melalui ilmu hudhurî. Meraih ilmu itu melalui tahapan
syariat (syariat), tarekat (thariqat), hakikat (haqiqat), dan makrifat (ma’rifat).
Dengan makrifat, segala hakikat dapat dipahami sehingga yang dikenali adalah
substansinya (jawhar), bukan hal-hal permukaan yang terindrai (aksiden,’aradh).
Dalam syairnya, Hamzah Fansûrî menulis:
Syariat akan katamu
Thariqat akan kerjamu
Haqiqat akan anggamu
Mangkanya sampai wahîd namamu
Ma'rifat itu ilmu yang mudah
Barang mendapat dia mengenali sudah
Citamu dari tempanya jangan kau ubah
Supaya washil tiada dengan susah
Jawhar nin mulia sungguhpun sangat
Akan orang muda kasih 'kan alat
Akan ilmu Allah hendak kau perdapat
Manakan sampai pulangmu rahat
Tuhan kita itu tiada bermakan
Lahirnya nyata dengan rupa insan
Man 'arafa nafsah suatu burhan
Fa-qad arafa rabbah terlalu bayan
Dengan sangat menyentuh, Hamzah Fansûrî mengingatkan bahwa
manusia harus karam dalam samudra, bukan dalam kolam. Maksudnya, manusia
tidak perlu terlena dengan dunia karena yang sesuai untuk manusia adalah
kenikmatan tiada batas dalam wasil Allah. Caranya adalah dengan tekun dalam
syariat dan senantiasa menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman kehidupan.
Manusia harus terbang membumbung menuju singgasana Ilahi. Caranya
adalah dengan 'uryan, yakni melepaskan diri dari segala, selain Allah. Inilah yang
dimaksud thayr uryanî.
Thayr uryanî unggas ruhani
Di dalam kandang hasrat Rahmanî
Warnanya pinggai terlalu shafî
299 Abdul Hadi WM, Tasawuf Yang Tertindas…, 335.
76
Thayr al-'uryani mabuk salîm
Mengenal Allah terlalu alîm
Demikian mabuk haruskan hakîm
Inilah amal Sayyid Abu al-Qasîm
Menurut Hamzah Fansûrî, thay uryanî ini adalah jiwa 'arif yang dirahmati.
Dianalogikan dengan burung adalah karena dia sedang terbang, menuju Ilahi. Burung
ini memiliki suara yang indah, bersih, mandinya di Sungai Salsabila.
Dalam puisi Hamzah Fansûrî ditekankan, selain syariat dianjurkan untuk
mengikuti tarekat. Suluk adalah jalan melepaskan kecenderungan duniawi. Manusia
harus konsisten dalam suluk. Supaya mendapatkan hakikat. Dengan demikian,
diraihnya makrifat. Bila mencapai derajat itu, manusia telah mendapatkan
pengetahuan sejati tanpa perantara300. Ilmu ini disebut ilmu hudhûri yang melampaui
batasan fisik301. Dalam keadaan itulah, diketahui keadaan Kebenaran sejati:
Zatnya tiada berkiri kanan
Zuhurnya da'im tiada berkesudahan
Tiada ber-jihat belakang dan hadapan
Di manakan dapat manzîl kau adakan
Jika kau dapat hakikat liqa'
Di ubun-ubun jangan jangan menyembah dliya
Karena Tuhan kita itu tiada ridha
Akan ilmu cahaya dan ilmu riya
Tuhan kita akan empunya wujûd
Di ubun-ubun tiada Ia qu'ûd
Jangan ditamsilkan amin dan quyûd
supaya washil dengan hakikat syuhûd
Kutipan syair di atas adalah sebagian dari gambaran Hamzah Fansûrî tentang
hakikat sejati. Jalan yang istimewa itu dimulai dengan langkah-langkah sederhana
dalam ibadah. Tekun dalam perintah fardu dan anjuran sunah, dan tegas dalam
membedakan halal dan haram adalah langkah awalnya. Syaratnya tidak
meninggalkan makna batin dari amalan-amalan itu.
Jika kau telah turut syari’atnya
Mangka kau dapat asal thariqat-nya
Ingat ingat akan hakikatnya
Supaya tahu akan makrifatnya
300 Iqbal, Rekonstruksi Pemikiran Relegius dalam Islam, (Bandung: Mizan, 2016),
19 301 Mehdi Haeri Yazdi, Menghadirkan Cahaya Tuhan: Epistemologi Illuminasionis
dalam Filsafat Islam, (Bandung: Mizan, 2003), 55
77
Manusia harus senantiasa menjaga nuraninya. Jangan sampai dunia
membuatnya terlena. Syariat Nabi Muhammad adalah pengingat. Sumber rezeki
haram harus dijauhi.
Fardu dan sunnat segera kerjakan
Itulah amal yang menerangkan jalan
Barang yang haram jangan kau makan
Supaya suci nyawa dan badan
Hadits ini dari Nabi al-habîb
Qala: Kun fi al-dunya ka-anna-ka gharîb
Barang siapa da’im akan dunia qarîb
Manakan dapat menjadi habib
Dalam syair-syairnya, Hamzah Fansûrî juga mengingatkan kepada manusia
supaya senantiasa mengenal hakikat dirinya. Manusia seperti setetes air dari samudra.
Sejatinya harus kembali ke samudra. Segala daya ‘aql, rûh, nafs, dan qalb harus
dikerahkan untuk kembali ke sana. Bila segala daya telah dicurahkan, akan selamat
saat mizân tiba.
Manusia hendaknya senantiasa bertobat. Juga harus membangun silaturahmi,
silaturahmi itu ibadah. Harus selalu yakin rezekinya telah diatur. Sibuk mencari harta
adalah jerat setan. Zina dan khayal harus dihindari juga. Kenikmatan dunia hanya
bayangan.
Nafsumu itu terlalu zalim
Pada Anggamu ia akan hakîm
Markabmu tiada ber-mu'allîm
Di manakan dapat engkau salîm
Sayangnya insan terlalu bebal
Disangkanya dunya lagi kan kekal
Nyaman matanya tidur di bantal
Akan salahnya tiada ia menyesal
Lemak manis terlalu nyaman
Oleh nafsu engkau tertawan
Sakarat al-mawt sulitnya jalan
Lenyap di sana berkawan-kawan
Hidup di dalam dunya umpama dagang
Datang mawsim kita kan pulang
La tasta khairuna sa'atan 'kan datang
Mencari ma'rifat Allah jangan alang-alang
Manusia adalah rahasia Tuhan. Harus menyadari keistimewaannya. Maka
dari itu, tidak patut tunduk pada nafsu dunia. Ketundukan mutlak hanya kepada Allah.
78
Posisi manusia di hadapan Allah persis seperti besi di hadapan tukang besi302.
Manusia harus senantiasa sadar bahwa kuasa Tuhannya amatlah tinggi. Dari itu
hendaknya manusia sadar bahwa tiada yang perlu dilakukan, kecuali dengan
mengikuti segala perintah-Nya.
Kekasih itu hendakkan nyawa
Itulah haluan yogya kau bawa
Jangan engkau takut akan tombak Jawa
Supaya orang jangan tertawa
Buangkan tirai berlapis lapis
Hampir-hampir pergi kau jalis
Pakaian mahbûb yogya kau labis
Supaya dapat mainmu manis
Manusia harus menyelam ke samudra Ilahi seperti ikan yang menyelam ke
laut dalam. Selain sarat amanat kemanusiaan sebagaimana telah dijelaskan di atas,
penjelasan tentang hakikat ketuhanan sarat di dalamnya. Di sana dijelaskan, Allah
hanya layak disebut “Dia” (Huwâ). Dia adalah Maha Esa (Ahad). Dengan kûn, jadilah
segala makhluk. Hamzah Fansûrî menganalogikan kondisi Tuhan itu sebagai laut
yang tenang. Kata kûn sebagai topannya sehingga menjelmalah segala macam
keberagaman. Hal itu dianalogikan dengan angka. Segala jumlah angka sejatinya
adalah dari satu dan merupakan kehadiran satu.
Sayangnya engkau terlalu lupa
Akan laut yang tiada berupa
Tandamu tuli lagi dan buta
Mabuk dan hijab lain mawta
Jika terkenal dirimu bapai
Engkaulah laut yang tiada berbagai
Ombak dan laut tiada bercerai
Musyahadah-mu sana jangan kau lalai
Pada hakikatnya, Dia Murni dengan Diri-Nya (Huwâ). Dalam kondisi ini,
Dia terlepas dari ‘itibar ketuhanan dan kemakhlukan. Status itu disebut maqam
Ahadiyah. Pada tahap selanjutnya, yakni maqam Wahidiyah telah mengandung tujuh
nama, yakni Hayy, ‘Ilm, Iradat, Qudrat, Kalâm, Samî', dan Bashîr. Bagian ini
dijelaskan dengan detail oleh Hamzah Fansûrî dalam prosanya, Asrâr.
Terdapat tiga prosa Hamzah Fansûrî, yakni Asrâr, Syarâb, dan al-Muntahî.
Tiga prosa itu telah ditransliterasikan oleh Syed Muhammad Naquib Al-Attas dalam
The Mysticism of Hamzah Fansûrî. Sebelumnya, Johan Doorenbos juga telah
mentransliterasi tiga prosa itu, tetapi Syed Muhammad Naquib Al-Attas melakukan
perbaikan atas kekurangan-kekurangan karya Johan Doorenbos. Asrâr adalah takwil
302 Syed Muhammad Naquib Al- Attas, The Mysticism of Hamzah Fansûrî, 261
79
yang dilakukan Hamzah Fansûrî atas salah satu syair pentingnya yang mengulas
tentang tujuh sifat Allah. Dalam Asrâr, penjelasan tentang hubungan antara kesatuan
dilakukan melalui penggunaan analogi-analogi yang mudah dipahami masyarakat
Melayu. Adapun Syarâb adalah penjelasan tentang empat perjalanan pesuluk, yakni
syariat Makna batin dari tiap perjalanan tersebut dijelaskan dengan baik. Dalam al-
Muntahî, dikemukakan pernyataan-pernyataan kaum sufi yang sebagiannya
merupakan pernyataan kontroversial.
Asrâr bertujuan menjelaskan tujuh sifat Allah, yakni Hayy, 'Ilmû, Murîd,
Qadîr, Kalâm, Samî', dan Basîr. Penjelasan ini menggunakan analogi-analogi
sehingga menjadi alat yang tepat dalam menjelaskan hubungan kesatuan dan
kemajemukan. Analogi-analogi yang digunakan adalah tanah dan perabotan, kayu
dan buah catur, cahaya dan sinarnya, laut dan ombak, buah bundar, biji dan
kandungan potensinya, cermin dan bayangannya, manusia dan atributnya, sungai dan
alirannya, air dan sifatnya, batu dan kepasifannya, besi dan tukang besi, dan lainnya.
Analogi merupakan kelaziman bagi ‘urafâ dalam menjelaskan pengalaman
hudhûrî. Mereka memilih objek tertentu untuk dijadikan analogi karena menemukan
keidentikan metafisis antara nama yang terpancar dalam pengalaman spiritual dengan
esensi objek yang dianalogikan303. Mengetahui analogi yang digunakan tanpa
memahami esensi objek analogi tentunya akan tidak berguna dalam studi tasawuf.
Terdapat berbagai analogi yang digunakan Hamzah Fansûrî dalam
menjelaskan ajarannya. Namun, tidak semua analogi yang digunakan adalah analogi
yang berada dalam status ontologi. Misalnya, analogi buah kelambir itu orientasinya
tentu adalah untuk menjelaskan signifikansi dan relasi syariat, tarekat, hakikat, dan
makrifat. Analogi ikan untuk menggambarkan status pesuluk yang fânâ304. Ada juga
suatu objek digunakan, tetapi tidak bersifat sebagai analogi, tetapi penjelasan
langsung. Misalnya, kata “cahaya”. Terkadang, kata tersebut bersifat analogis,
terkadang kata tersebut bersifat langsung.
Dalam syair-syair Hamzah Fansûrî terdapat sangat banyak analogi.
Orientasinya ada untuk ontologi, maupun selainnya. Dalam tiga prosa juga
terkandung banyak analogi yang digunakan Hamzah Fansûrî dalam menjelaskan
ajaran-ajarannya. Asrâr adalah karya Hamzah Fansûrî yang sangat penting karena dia
sendiri mentakwilkan puisinya dalam bentuk prosa sehingga ajarannya menjadi
makin jelas. Namun, penjelasan ajaran-ajaran yang digunakan tetap saja
menggunakan analogi. Oleh sebab itu, apabila dapat menyingkap ajaran inti
(ontologi) Hamzah Fansûrî yang diungkapkan melalui analogi yang terkandung
dalam karya pentingnya Asrâr, ajaran Hamzah Fansûrî dapat menjadi terang.
Dalam Asrâr, analogi untuk ontologi yang digunakan Hamzah Fansûrî
mencakup berbagai objek utama, yakni cahaya, laut, tanah, dan kayu. Disebut objek
utama karena empat analogi itu secara digunakan untuk menerangkan Bâsîth sebagai
Wujûd yang Tunggal. Relasi Bâsîth dengan makhlûqat orientasinya untuk
303 Miswari, “Filosofi Komunikasi Spiritualitas: Huruf Sebagai Simbol Ontologi
Dalam Mistisme Ibn ’Arabî,” Al-Hikmah 9, no. 14 (2017): 12–30. 304 Ikan tongkol dianalogikan sebagai kondisi fânâ pesuluk. Ikan gajahmina
dianalogikan sebagai kondisi fânâ yang lebih dalam. Ikan kerapu punya analogi dalam
konteks yang berbeda yakni menggambarkan sesuatu yang bisa mirip, tetapi berbeda.
80
mempertegas tentang ketunggalan Haqq Ta’âlâ. Sementara analogi-analogi lain
memang masih berada dalam status ontologis, tetapi digunakan dalam rangka
menjelaskan relasi Bâsîth dengan makhlûqat. Analogi-analogi ini disebut analogi
sekunder. Objek-objek yang digunakan dalam analogi sekunder adalah manusia,
cermin, batu, air, sungai, dan besi305.
Sementara itu, Syarâb adalah prosa lainnya dari Hamzah Fansûrî yang
membahas tentang jalan menuju makrifat. Kitab tersebut juga merupakan bentuk
kepekaan Hamzah Fansûrî dengan menuliskannya dalam bahasa Melayu. Hal ini
karena pada masa itu kitab Melayu yang menjelaskan pedoman menempuh jalan
spiritual sangat dibutuhkan. Titik tekan dalam karya itu agar manusia tidak terperdaya
oleh kenikmatan duniawi.
Hamzah Fansûrî menegaskan dalam Syarâb bahwa syariat, tarekat, hakikat,
dan makrifat adalah tahapan-tahapan integratif menuju wasil Allah. Karya itu juga
mengandung berbagai analogi untuk memudahkan pemahaman pembacanya.
Mengerjakan segala ibadah fardu adalah prasyarat mutlak. Tobat dari segala maksiat
adalah niscaya. Manusia tidak dibenarkan hidup berlebihan. Tidak ada yang lebih
perlu dilakukan manusia, kecuali berusaha mendekatkan diri pada Allah. Selain itu,
hanyalah kesia-siaan.
Di dalam Syarâb juga dijelaskan secara sistematis tentang konsep ta’ayyûn
yang digagas Hamzah Fansûrî. Konsep tersebut merupakan bagian penting dari
pemikiran Hamzah Fansûrî. Inti gagasannya adalah untuk menegaskan bahwa inti
hakikat adalah satu wujûd. Hamzah Fansûrî menganalogikan pemahaman itu dengan
menggunakan berbagai objek, di antaranya air yang berada dalam berbagai kondisi,
seperti menjadi uap, menjadi awan, menjadi hujan, menjadi sungai, dan sebagainya,
tetapi pada hakikatnya adalah air.
Karya al-Muntahî yang berisi sangat banyak kutipan Al-Qur’an, hadis,
pernyataan para sahabat nabi, dan pernyataan-pernyataan kaum sufi. Kitab al-
Muntahî dapat dikatakan sebagai karya Hamzah Fansûrî yang sangat kontroversial.
Pemaknaan nash dalam karya itu berbeda dengan dipahami secara umum. Hamzah
Fansûrî memilih jalur esoteris untuk memaknainya. Namun demikian, sebenarnya
bila telah menerima prinsip ajaran dalam Syarâb dan Asrâr, pernyataan-pernyataan
di dalam al-Muntahî akan dapat dimaknai secara positif. Hadis, seperti “Barang siapa
menilik kepada sesuatu, jika tiada dilihatnya Allah di dalamnya, maka ia itu sia-sia”
dan dan pernyataan sahabat, seperti “Tiada kulihat sesuatu melainkan kulihat Allah
di dalamnya” (Alî bin Abî Thalib) akan dimaknai sebagai dukungan atas gagasan
Wujudiah.
Sistem penalaran dan ajaran sufi Wujudiah memang berbeda dengan cara-
cara penalaran umum karena kaum sufi menjadikan penyingkapan batinnya sebagai
landasan pengetahuan. Dalam al-Muntahî juga Hamzah Fansûrî menjelaskan prinsip
Wujudiah dengan menggunakan analogi. Misalnya, buah limau, daun, buah, batang,
dan kulit memiliki banyak penamaan, tetapi sejatinya adalah limau. Demikian juga
beraneka ragam makhluk di alam, sejatinya berasal dari satu wujûd.
Pernyataan kontroversial, seperti, “Akulah al-Haqq,” dari Abû Mansûr al-
Hallaj, ''Maha suci aku, tiada yang lebih lebih besar dari diriku,'' dari Abû Yazid al-
305 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 287.
81
Bistamî, ''Tiada di dalam jubahku ini melainkan Allah'', dari Junayd al-Baghdadî,
''Dhat Allah yang Qadim itulah dhatku sekarang,” dari Mas’ûdî, ''bahwa akulah
Allah,'' ungkapan Sayyid Nasîmî, dan beberapa ungkapan lainnya dikutip Hamzah
Fansûrî dalam al-Muntahî306. Karena itulah, selain karena analogi-analogi yang
digunakan, yang membuat Hamzah Fansûrî dikritik keras oleh Nûr al-Dîn al-Ranîrî
karena mengakomodir gagasan-gagasan kontroversial dari sufi-sufi yang dianggap
mulhithî.
B. Prinsip Dasar Ajaran Hamzah Fansûrî
Terdapat beberapa prinsip penting dalam ajaran Hamzah Fansûrî, yakni
membahas tentang iktikad para pesuluk yang dibedakan dengan iktikad para
mutakallimîn, seperti pengakuan bahwa wujûd itu bersifat univokal. Dalam
pembahasan Sifat Haqq Ta’ala, Hamzah Fansûrî menjelaskan tentang tujuh Sifat
utama, yakni Hayy, 'Ilmû, Irâdat, Kâlâm, Sâmî', dan Basyar. Sementara Ta’ayun
sebagai pembahasan manifestasi Ilahi terbagi menjadi tujuh tingkatan, yakni
Ahadiyah, wahdah, wahidiyah, ‘alam arwah, ‘alâm mitsal, alâm ajsâm, dan ‘alam
insân. Hamzah Fansûrî memperingatkan kepada manusia bahwa hidup di dunia
umpama anak dagang, hadir sejenak dan harus benar-benar serius dalam
mempersiapkan bekal kembali.
5. Iktikad Para Pesuluk
Dalam Asrâr, Hamzah Fansûrî mengatakan bahwa kesamaan antara
mutakallimîn dan ‘urafâ307 adalah pada kesepakatan bahwa Dzat Haqq Ta’âlâ tidak
dapat dijangkau siapa pun, termasuk ‘urafâ, nabi, dan malaikat al-muqarrabîn. Oleh
karena itu, dalam hal ini dia ingin membagi perbedaan antara pandangan ‘urafâ dan
mutakallimîn308. Hamzah Fansûrî menerangkan bahwa, dalam pandangan ‘urafâ,
Dzat Haqq Ta'âlâ dengan wujûd-nya adalah satu. Wujûd dan Ilmu-Nya adalah satu.
Dzat Bâsîth dan wujûd Bâsîth adalah satu. Hamzah Fansûrî menjelaskan, menurut
para mutakallimîn, wujûd Bâsîth dengan wujûd alam itu berbeda. Hamzah Fansûrî
mengatakan, bila pemahaman mereka demikian, itu berkonsekuensi pada
keterbatasan wujûd Haqq Ta'âlâ309. Setidaknya, batasnya adalah wujûd alam, dengan
sanggahannya kepada mutakallimîn dan menegaskan pandangannya bahwa wujûd itu
adalah satu, yang diumpamakan dengan matahari dan sinarnya. Juga diumpamakan
306 Fansûrî, “Al-Muntahî,”…, 334–335. 307 Hamzah Fansûrî dalam pembahasan ini, menggunakan istilah ‘’urafâ’ dengan
‘ahlû sûlûk’. Penulis mengganti istilah tersebut karena para mutakallimîn juga sebagiannya
menjadi pesuluk. Penulis menduga Hamzah Fansûrî menggunakan istilah ‘ahlû sûlûk’
karena dalam hal ini dia melibatkan dirinya sehingga tidak mengklaim dirinya sebagai
seorang yang telah mencapai penyingkapan spriritual tinggi yang disebut dengan seorang
‘’arîf”. 308 Nasution, “Termination of Wahdatul Wujud in Islamic Civilization in Aceh: Critical
Analysis of Ithaf Ad-Dhaki, The Works of Ibrahim Kurani.”,,,, 401. 309 Humaidi, “Mystical-Metaphysics: The Type of Islamic Philosophy in Nusantara in
the 17th-18th Century.”,,,, 90.
82
dengan cermin dan bayangannya. Maka dari itu, Hamzah Fansûrî telah menegaskan
pahamnya adalah Wahdah Al-Wujûd atau dalam istilah Melayu disebut Wujudiah.
Selanjutnya, Hamzah Fansûrî kembali menegaskan pandangan Wujudiah yang
dipegangnya juga dengan menunjukkan perbedaan pandangan antara mutakallimîn
dengan ‘‘urafâ. Para mutakallimîn dalam memaknai basmalah, bahwa Rahman Allah
diberikan kepada seluruh makhluk di dunia, sementara Rahîm dikhususkan kepada
hamba terpilih di akhirat310. Sementara Hamzah Fansûrî mengatakan, pandangan
dirinya dan ‘urafâ lainnya bahwa Rahman berarti Bâsîth sebagai Wujûd Mutlak
memberikan wujûd kepada seluruh alam semesta. Sementara wujûd itu dalam
masing-masing tingkatan tidak terpisah dengan sumber wujûd yang berarti wujûd itu
adalah satu kesatuan, wahdah al-wujûd. Sementara al-Rahîm hanya diberikan kepada
para nabi, ‘‘urafâ dan shalihîn.
Selanjutnya, Hamzah Fansûrî mengatakan, dengan mengutip beberapa bagian
awal surah Ar-Rahman, bahwa al-Rahman mengajarkan Al-Qur’an, dan mengajarkan
manusia dapat membuat persepsi (bayân). Oleh karena itu, kemampuan memahami
alam atau munculnya sekalian alam esensinya adalah nafas al- rahman. Manusia
yang dapat memahami hakikat nama-nama dalam alam dijadikan dari rupa al-
Rahman. Al-’Ayan al-tsabîtah adalah sesuatu yang berada dalam napas al-Rahman.
Dari-Nyalah segala kemajemukan alam bersumber311. Hamzah Fansûrî mengatakan
bahwa Rahman itu adalah Wujûd. Sifat sifat lainnya juga dari Kesatuan Wujûd
sehingga segala yang muncul dari al-‘ayan al-tsabitah meskipun memiliki tingkatan
yang berbeda, tetap merupakan bagian dari Kesatuan Wujûd312.
Bâsîth sebagai Wujûd Mutlak memberikan wujûd pada sekalian alam melalui
rahmat Rahman sehingga segala wujûd alam merupakan manifestasi wujûd Haqq
Ta’âlâ. Hamzah Fansûrî menganalogikan tajali ini seperti tanah yang dijadikan
berbagai bentuk, seperti kendi, buyung, periuk, tempat, dan bejana. Bentuknya
memang beragam, tetapi hakikatnya adalah tanah.
Kemajemukan alam semesta yang dianalogikan dengan tumbuhan,
digambarkan Hamzah Fansûrî muncul dari ‘Ilmû Bâsîth yang dianalogikan dengan
tanah, dan Wujûd Bâsîth dianalogikan dengan air. Dalam pertemuan wujûd dan ilmu
menjelma alam semesta, seperti dalam pertemuan air dan tanah terbit tumbuh-
tumbuhan. Aneka macam tumbuhan, aneka warna, dan aneka rasa buahnya menjelma
sebagai keberagaman dari air.
Demikian juga keanekaragaman alam, sebagai bentuk, semuanya bersumber
dari Wujûd Haqq Ta’âlâ. Demikian pula, segala yang dianggap baik, segala yang
dianggap jahat, muncul dari Haqq Ta’âlâ. Hamzah Fansûrî menambahkan, bila suatu
keindahan dan kebaikan muncul dari penilaian manusia, berarti kadar Jamal lebih
dominan. Sementara hal-hal yang dinilai sebagai keburukan didominasi oleh kadar
Jalâl. Meskipun demikian, pada setiap hal terkandung Jamal dan Jalâl dalam
dominasi kadar yang berbeda-beda313.
310 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”,,,, 263. 311 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”,,, , 263. 312 Syaifan Nur, “Kritik Terhadap Pemikiran Tasawuf Al-Raniri.”,,,, 137. 313 Drewes and Brakel, The Poems of Ḥamzah Fansûrî…, 121.
83
Sebagai aktualitas dari al-‘ayan al-tsabitah, alam semesta adalah dalam
lingkup pengetahuan Haqq Ta’âlâ. Hamzah Fansûrî dalam menjelaskan Bâsîth
sebagai ‘Alîm dan alam semesta sebagai yang diketahui (ma’lûm) menganalogikan
‘alîm sebagai laut sementara ma’lûm sebagai awan ketika menguap di udara, sebagai
hujan ketika turun dari langit, dan sebagai sungai ketika mengalir di darat. Meskipun
memiliki berbagai rupa dan bentuk, hakikatnya adalah air (laut). Segala yang berupa
dan berwarna adalah yang zahir dan dapat disebut ma’lûm. Indra manusia sangat
terbatas sehingga hanya dapat mengidentifikasi sesuatu yang memiliki bentuk dan
warna. Sementara realitas itu sendiri adalah satu kesatuan, menyeluruh namun tidak
mampu diindrai sehingga dapat disebut sebagai batin.
Sementara dalam menjelaskan relasi antara Qasim (yang dibagi) dan maqsum
(bagian-bagian). Adapun Qasim tentunya adalah Wujûd Mutlak sementara maqsum
adalah wujûd alam semesta yang majemuk. Qasim dianalogikan dengan laut,
sementara maqsum dianalogikan dengan ombak. Sekalipun beragam bentuk, ombak
itu sejatinya adalah laut. Sekalipun beragam penjelmaan alam semesta sejatinya
adalah satu wujûd tunggal314.
Sekalipun menegaskan bahwa wujûd alam semesta adalah bagian dari
Kesatuan Wujûd, Hamzah Fansûrî menegaskan bahwa wujûd yang ditangkap pada
alam semesta itu hanyalah wujûd wahmî, yakni wujûd yang dimunculkan persepsi.
Maksud ini dapat dijelaskan melalui sistem filsafat yang mana filsafat Ibn Sînâ
mengatakan bahwa wujûd yang dapat dipersepsi pada alam hanyalah tambahan dari
mâhiyâh-nya. Sementara wujûd sejati dari realitas dalam makna Kesatuan Wujûd
diperoleh melalui mukasyafah315.
Dalam mukasyafah, wujûd sejati sebagai Kesatuan Wujûd dapat dikenal. Jalan
untuk mencapai mukasyafah adalah dengan pelatihan spiritual yang tertib. Syariat
harus dijalankan dengan baik supaya memperoleh syarat tarikat. Dengan tarikat
dicapailah hakikat. Melalui hakikat tercapailah makrifat316. Namun, usaha
memperoleh muksyafah sehingga menghasilkan makrifat hanya akan berhasil dengan
karunia Ilahi317.
Hamzah Fansûrî menjelaskan dengan tertib tahapan tahapan menempuh jalan
spiritual dalam Syarâb al-Asyiqîn. Akan tetapi, Hamzah Fansûrî sendiri mengatakan
bahwa untuk memahami ajarannya dengan baik adalah dengan mempelajari syair-
syairnya dengan baik. Untuk dapat memahami syair Hamzah Fansûrî dengan baik
perlu mempelajari Asrâr karena dalam karya tersebut Hamzah Fansûrî melakukan
syarah sendiri atas beberapa syairnya. Di samping itu, Shams al-Dîn al-Sumatranî
314 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”… , 252. 315 Yazdi, The Principles of Epistemology in Islamic Phlosophy: Knowledge by
Presence…, 162. 316 Rohaimi Rastam, Yusri Mohamad Ramli, dan Mohd Syukri Yeoh Abdullah,
“Penilaian Terhadap Pengajaran Syariat Islam Oleh Al-Hallaj, Hamzah Al-Fansuri, dan
Shamsuddin Al-Sumatera’i,” International Journal of Islamic Thought 12, no. 1 (December
1, 2017): 59–71, http://www.ukm.my/ijit/wp-content/uploads/2017/11/IJIT-Vol-12-Dec-
2017_6_59-71. 317 Izutsu, Struktur Metafisika Sabzawari…, 65.
84
juga mensyarah beberapa syair Hamzah Fansûrî sebagaimana telah berhasil dihimpun
oleh Ali Hasjmy dalam Ruba'i Hamzah Fansûrî318.
Hamzah Fansûrî mengatakan, dalam pandangan mutakallimîn, bila seseorang
telah mengucapkan kalimat syahadat dengan lisannya, tidak ada alasan untuk
mengatakan dia bukan muslim. Akan tetapi, bagi'‘urafâ, syahadat berarti dapat
menyaksikan langsung dengan kasyaf sehingga dapat menemukan Kesatuan Wujûd
dan mengenal nama-nama Ilahi dalam setiap entitas majemuk yang semua ini
terhimpun dalam al-insân al-kâmil, yakni Nabi Muhammad319.
Segala makhlûqat berasal dari 'ilmû Haqq Ta’âlâ. Disebut rûh karena hidup,
disebut nûr karena memancar. Disebut ‘aql karena dapat diketahui. Disebut Qalâm
karena tersurat di lawh al-mahfûdz. Nur Muhammad adalah sumber nyawa dan Nabi
Adam adalah sumber jasad. Himpunan keduanya disebut insân320. Hamzah Fansûrî
mengatakan manusia tidak memiliki kehendak apa pun. Untuk mendapatkan
kehendak, manusia harus punya ilmu. Untuk mendapatkan ilmu harus memiliki
kehidupan. Untuk memiliki kehidupan harus memiliki wujûd. Sementara wujûd
hanya Haqq Ta’âlâ. Pandangan kebersyaratan sifat-sifat tersebut adalah bersumber
dari epistemologi Wahdah al-Wujûd yang dibangun oleh Ibn ‘Arabî321.
Ketinggian status 'urafâ digambarkan Hamzah Fansûrî dalam contoh tentang
bagaimana keduanya berpandangan tentang rezeki. Bagi mutakallimîn, klasifikasi
mencari rezeki hanya sebatas membolehkan yang halal dan melarang yang haram.
Sementara bagi ‘urafâ mencari rezeki saja tidak dibenarkan karena itu artinya
mencari duniawi, berkebutuhan, dan bergantung pada aspek duniawi. Namun, bila
rezeki itu hadir kepadanya, tidak boleh ditolak. Hamzah Fansûrî mengajarkan kepada
pesuluk untuk tidak memperbanyak makan dan meminimalkan pergaulan sesama
manusia. Pesuluk tidak dibenarkan memiliki ketertarikan kepada duniawi. Dalam
itikad pesuluk, tidak boleh ada dualitas. Konsentrasinya harus hanya kepada Haqq
Ta’âlâ saja. Bila masih beritikad pada dualitas, itu termasuk kesyirikan322.
Bagi ‘urafâ, kefakiran adalah melihat dan menyadari bahwa makhuk-makhluk
itu sama sekali tidak memiliki wujûd. Kesadaran ketiadaan wujûd makhluk itu dapat
menghantarkan pada fânâ. Ke-fânâ-an dalam pandangan Hamzah Fansûrî adalah
melampaui Athar, melampaui af'al, melampaui Asma', dan melampaui sifat. Dalam
analogi Hamzah Fansûrî, fânâ harus seperti laron yang lenyap terbakar api, sama-
sekali tidak lagi mampu mengidentifikasi dualitas323. Fânâ bukan seperti besi yang
318 Hasjmy, Ruba’i Hamzah Fansûrî…, 12. 319 Syarif Hidayatullah, “Perspektif Filosofis Sir Muhammad Iqbal Tentang Pendidikan
Islam,” Jurnal Pendidikan Islam 2, no. 2 (January 1, 1970): 419, http://ejournal.uin-
suka.ac.id/tarbiyah/index.php/JPI/article/view/1154; Rusdiana, “Pemikiran Ahmad Tafsir
Tentang Manajemen Pembentuk Insan Kamil.” 320 Hadi, Tasawuf Yang Tertindas: Kajian Hermeunetik Terhadap Karya Hamzah
Fansûrî, 36. 321 Bagir, Semesta Cinta, 193. 322 Braginsky, “Some Remarks on the Structure of the ‘Sya’ir Perahu’by Hamzah
Fansûrî,” 76. 323 Abdul W.M Hadi, Hamzah Fansûrî: Risalah Tasawuf dan Puisi-Puisinya
(Bandung: Mizan, 1995), 53.
85
terbakar api, sebagaimana dianalogikan Jalal al-Dîn Rûmî324 karena dalam kondisi
demikian, dualitas besi dan api masih dapat diidentifikasi.
Fânâ bagi Hamzah Fansûrî adalah tanggalnya ketertarikan kepada apa pun
selain Haqq Ta’âlâ. Ini bukan berarti sama sekali tidak boleh memiliki fasilitas
duniawi, tetapi tidak boleh berkecenderungan sama sekali kepada duniawi.
Menghindari perkara lahiriah adalah dengan syariat, menghindari perkara batiniah
adalah dengan hakikat. Syariat dan hakikat itu tunggal. Kesatuan syariat dan hakikat
dianalogikan dengan buah kelambir. Syariat adalah kulitnya, tarekat seperti
tempurung, hakikat seperti isinya, dan makrifat seperti minyaknya.
Dalam Syarâb, Hamzah Fansûrî menjelaskan tentang tujuh status jalan
spiritual yakni, syariat, tarekat, hakikat, makrifat, tajali Dzat, Sifat-sifat, cinta, dan
syukur. Tahap-tahap ini semuanya harus dilalui pesuluk untuk menjadi 'arîf. Dalam
keberagaman wujûd, namun hakikatnya adalah satu, di dalam al-Muntahî,
dianalogikan Hamzah Fansûrî dengan limau. Sekalipun ada daun, buah, dan batang,
keseluruhannya disebut limau. Perbedaan-perbedaan hanya pada penamaan saja,
sementara hakikatnya adalah satu. Analogi dalam hal ini, analogi lainnya yang dibuat
Hamzah Fansûrî adalah perumpamaan dua nama antara “susu” dan minyak sapi.
Penamaannya berbeda, tetapi acuannya sama.
Kesatuan Wujûd antara Haqq dan khalq juga dianalogikan dengan hubungan
jasad dengan rûh. Rûh tidak berada di dalam jasad. Tidak pula rûh berada di luar
jasad. Hubungan ini dianalogikan juga seperti hubungan permata dan kilauannya.
Kilauan itu tidak berada di dalam permata. Tidak pula kilauan itu di luar permata. Hal
ini untuk menunjukkan bahwa Haqq Ta’âlâ itu dekat dengan makhluk-Nya, tetapi
bukan bermakna mengenai jarak, tetapi bahwa Haqq Ta’âlâ meliputi segala
sesuatu325.
Dengan kondisi demikianlah, ‘urafâ menjadi kesulitan membedakan antara
Haqq dan khalq sehingga Abû Mansûr al-Hallaj mengatakan, "Anâ al-Haqq, Akulah
Kebenaran Mutlak", Abû Yazid al-Bistamî mengatakan, "Subhânî, Maha Suci Aku,
tiada yang lebih besar daripada aku" atau Junayd al-Baghdadî mengucapkan, “Tiada
di dalam jubah ini melainkan Allah", al-Nasîmî mengatakan, "Bahwa akulah Allah"
dan al-Mas'udî mengatakan, "Dzat Allah yang Qadim itulah Dzat-ku sekarang".
Berbagai syatahat itu hanya diucapkan dalam kondisi fânâ. Bila itu diucapkan di luar
kondisi tersebut, itu tidak dibenarkan. Bagaimana ‘urafâ tidak dapat menghindari
syatahat, padahal dapat menimbulkan kebingungan, dan kesalahpahaman, Hamzah
Fansûrî menjelaskannya dengan mengutip ungkapan al-Shiblî, yang menyatakan
bahwa seorang dalam kondisi fânâ seperti katak di dalam laut. Bila menutup
mulutnya, dia dapat mati. Bila membuka mulutnya, air laut memasuki mulutnya. Dan
itu juga dapat menyebabkan kematian.
324 Schimmel, Mystical Dimensions of Islam (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust,
2008), 24. 325 Saliyo, “Selayang Pandang Harmonisasi Spiritual Sufi Dalam Psikologi
Agama.”…, 5-11.
86
6. Sifat Haqq Ta’ala
Segala kemajemukan yang sejatinya berasal dari satu, sebagaimana dalam al-
Muntahî dianalogikan oleh Hamzah Fansûrî dengan air yang menumbuhkan berbagai
jenis buah dengan berbagai warna, dan aneka ragam rasa. Sejatinya adalah satu, lalu
menjelma keberagaman. Sebagaimana berbagai bentuk ombak dengan adanya angin,
demikian juga menjelma berbagai jenis makhlûqat. Bila angin berhenti, segalanya
bentuk ombak kembali ke laut. Demikian juga segenap kemajemukan kembali
sehingga sejatinya yang kekal hanya Wajah Allah326.
Dari kesatuan muncul keberagaman, dan pada keberagaman itu hakikatnya
adalah kesatuan wujûd327. Jalan memahaminya adalah dengan mengenal diri, "Barang
siapa yang mengenal dirinya, akan mengenal Rabb-nya". Karena pengenalan hakikat
diri itulah yang menjadi landasan, menjadi paradigma mengenal Tuhan. Hakikat diri
bukanlah perangkat-perangkat aksidental karena itu semua adalah keberagaman yang
muncul dari analisis mental. Konsep “Tuhan” adalah konsep yang meniscayakan
keberadaan konsep “hamba”. Dualitas ini adalah konsekuensi analitis akal.
Sementara sumbernya atau landasannya adalah mengenal diri yang mana hakikatnya
adalah wujûd yang satu dan berasal dari Wujûd Haqq Ta’âlâ 328.
Sementara itu, Haqq Ta’âlâ bukan aksiden (dan bukan pula genus) sehingga
tidak dapat diidentifikasi dalam sistem empirik-analitik329. Haqq Ta’âlâ tidak
mengambil tempat. Segala yang bertempat adalah yang memiliki aksiden. Segala
yang memiliki aksiden itu sifatnya terbatas. Sementara Haqq Ta’âlâ tiada berbatas.
Zahir adalah dia, batin juga Dia. Dia adalah awal, Dia juga akhir330. Segala makhluk
memperoleh wujûd dari Haqq Ta’âlâ. Semuanya mengada dengan pemberian wujûd
dari-Nya. Persyaratan memperoleh wujûd adalah dengan ikrar sejak alam rûh.
Mempertahankan wujûd yang terjadi secara terus menerus adalah dengan zikir.
Semua maklûqat berzikir kepada-Nya setiap waktu, siang dan malam. Manusia
mempertahankan hubungan dengan Haqq Ta’âlâ adalah dengan syariat. Hamzah
Fansûrî sangat menekankan pentingnya syariat. Siapa yang melepaskan diri dari
syariat maka sesatlah dia331.
Mengenal Dzat Haqq Ta’âlâ adalah suatu kemustahilan sehingga pengenalan
terbaik adalah melalui sifat-sifat. Sama seperti mengenal seseorang, cara terbaiknya
adalah dengan mengenal Sifat-sifat-Nya. Misalnya, seseorang yang suka memberi
disifatkan dengan rahman. Mereka yang jujur disebut shiddiq. Pengenalan sifat-sifat
Haqq Ta’âlâ adalah melalui alam semesta. Pengenalan tersebut bukan tentang
kondisi aksiden. Pengenalan aksiden hanya sebatas pengenalan indrawi benda-benda
itu sendiri332. Pengenalan Sifat-sifat Haqq Ta’âlâ adalah mengenal pada esensinya.
Pengenalan tersebut hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah mencapai
326 Al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansûrî…, 167. 327 Jabir, Wahdah Al-Wujûd Ibn ‘Arabî Dan Filsafat Wujûd Mulla Sadrâ…, 16. 328 Izutsu, Sufism and Taoism: A Comparative Study of Key Philosophical Concepts…,
36. 329 Kindî, On First Phylosophy…, 14. 330 Drewes dan Brakel, The Poems of Ḥamzah Fansûrî…, 18. 331 Al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansûrî…, 302. 332 Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri…, 130.
87
mukasyafah. Dalam pengalaman tersebut bukan tentang kondisi aksiden. Pengenalan
aksiden hanya sebatas pengenalan indrawi benda-benda itu sendiri333.
Hanya dengan jalan tersebut segala Nama dan Sifat dapat dikenal melalui
hakikat semesta. Sementara selain itu bukanlah pengetahuan sejati. Bahkan,
penjelasan-penjelasan tasawuf filosofis, khususnya yang diekspersikan melalui puisi
maupun prosa adalah menggunakan analogi334. Menurut Hamzah Fansûrî, analogi-
analogi tersebut sebenarnya hanya pelambangan saja dari pengalaman 'arifîn.
Namun, Ibn ‘Arabî mengatakan bahwa analogi-analogi yang digunakan ‘urafâ untuk
menjelaskan pengalaman kasyaf mereka memiliki relasi metafisika. Maksud Ibn
‘Arabî adalah, penggunaan sesuatu untuk menggambarkan sesuatu memiliki
keidentikan esensi antara keduanya karena ‘urafâ memang telah dapat menangkap
hakikat dari hal-hal yang digunakan sebagai analogi. Maka dari itu, analogi-analogi
yang digunakan tersebut memang dapat menjelaskan pengalaman kasyaf. Dengan
demikian, pengenalan atas Sifat-sifat adalah jalan terbaik mengenal Allah. Hamzah
Fansûrî menjelaskan tujuh sifat Haqq Ta’âlâ, yakni Hayat, Ilmû, Iradat, Qudrat,
Kalam, Samî', dan Basar. Haqq Ta’âlâ itu Qayyim. Dia berdiri dengan sendirinya.
Sementara yang lainnya tegak karena Dia yang menegakkan. Haqq Ta’âlâ dan
sifatnya adalah satu.
Sifat pertama adalah Hayy, yakni hidup. Hidup harus menjadi sifat pertama
karena hanya dengan hidup maka sifat-sifat yang lain terjadi. Apabila tidak hidup,
berarti mati. Analoginya orang mati maka sifat-sifat lainnya menjadi mustahil. Orang
yang mati tidak dapat mengetahui, tidak dapat berkehendak, tidak dapat mendengar,
tidak dapat melihat, dan seterusnya. Misalnya, orang mati tentunya tidak memiliki
sifat. Haqq Ta’âlâ bersifat hidup. Sebab itu, Dia dapat memberikan hidup kepada
makhlûqat. Hanya yang memiliki yang dapat memberikan. Bila Dia tidak hidup,
mustahil dapat memberi kehidupan335.
Sifat kedua adalah 'Ilmû, yakni mengetahui. Dengan sifat ini Haqq Ta’âlâ
dapat mengetahui Diri-Nya. Dari aktivitas ini muncul 'alim, ma'lûm, dan "ilmû.
Sebagai yang mengetahui Dia disebut 'alim. Sebagai yang diketahui, Dia disebut
ma'lûm. Aktifitas pengetahuan disebut 'ilmû. Sebagai yang mengetahui disebut awal,
sebagai yang diketahui disebut akhir. Sebagai yang mengetahui disebut Batin, sebagai
yang diketahui disebut Zahir. Sebagai Zahir maka dia menjadi dapat dikenali oleh
manusia336.
Sifat ketiga adalah Irâdat yang artinya Berkehendak. Haqq Ta’âlâ adalah
perbendaharaan tersembunyi. Dengan Iradât-Nya untuk dikenal. Maka dari itu, Dia
ber-'isti'dad dengan ‘Ilmû-nya sehingga menjelmalah makhlûqat Sebab itu, dia yang
sebelumnya tersembunyi menjadi teraktual. Dia yang sebelumnya Batin menjadi
Zhahir. Hamzah Fansûrî menganalogikan kondisi tersembunyi seperti biji337.
333 Yazdi, The Principles of Epistemology in Islamic Phlosophy: Knowledge by
Presence, 87. 334 Abdul Hadi WM, Hermeneutika Sastra Barat Dan Timur, (Jakarta: Sadra Press,
2014), 167. 335 Abdul Hadi WM, Hermeneutika Sastra Barat Dan Timur…, 181. 336 Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri…, 120–121. 337 Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri…, 132.
88
Padanya terkandung potensi batang, daun, dan buah, selanjutnya teraktualisasi. Cara
mengaktualisasikan makhlûqat adalah dengan 'Amr-Nya. Sebagaimana bunyi Al-
Qur’an Surah Yasin: 38, "Sesungguhnya 'Amr-Nya ketika menginginkan kejadian
sesuatu, dikatakan kepada-nya (lahû), 'jadilah”'. Oleh karena itu, bila pun sesuatu
belum menjelma, tetap dikatakan lahû yang berarti memang sudah sedia, tetapi masih
dalam Ilmu-Nya. Maka dari itu, dengan 'Amr-Nya, dikatakan pada ‘lmû-Nya
“jadilah”. Dengan demikian, teraktualisasikanlah kemajemukan semesta338.
Sifat keempat adalah Qudrat. Dia berkehendak atas segala sesuatu339. Dia
memberikan batasan-ketentuan, dan ketetapan kepada setiap sesuatu. Karena itu,
tidak ada apa pun dan siapa pun yang dapat mengingkari ketetapan-Nya. Sebab itu,
tidak ada apa pun yang dapat melanggar ketetapan-Nya. Tidak ada pilihan, kecuali
menerima segala kadar dan ketetapan karena pada setiap ketetapan dan ketentuan itu
adalah kebaikan. Semua itu adalah dari Haqq Ta’âlâ. Pada dasarnya, semua adalah
kebaikan karena datang dari-Nya. Sifat kelima adalah Kâlâm. Hamzah Fansûrî
menolak pandangan Mu'tazilah yang menyatakan bahwa kalam Allah itu makhluk
yang baharu. Hamzah Fansûrî sepakat bila kalam yang baharu adalah yang turun
kepada Nabi Muhammad dan mushaf Al-Qur’an. Sementara Kâlâm dalam makna
ontologisnya hanya Allah yang tahu. Dan pastinya, Haqq Ta’âlâ dan Kâlâm itu tidak
seperti manusia dengan ucapannya.
Sifat keenam adalah Sâmî'. Haqq Ta’âlâ mendengar tidak sama seperti
manusia mendengar. Manusia mendengar, lalu mendapatkan pengetahuan baru
sehingga terjadi perubahan pada pengetahuannya. Sementara ‘Ilmû Haqq Ta’âlâ itu
tetap, tidak pernah berubah. Haqq Ta’âlâ mendengar apa pun di semesta, bahkan
hingga hal kecil yang terbesit di dalam hati manusia340. Sifat ketujuh adalah Basyar.
Haqq Ta’âlâ tidak membutuhkan mata untuk melihat. Dia melihat dengan ‘Ilmû-Nya.
Demikian juga dengan penglihatan-Nya, tidak terjadi perubahan pada Ilmû -Nya.
Dengan banyaknya sumbangan kajian filosofis yang telah dipelajari Hamzah
Fansûrî maka sekalipun lebih banyak mengemukakan pandangannya melalui puisi,
Hamzah Fansûrî telah dapat membangun sistem Wujudiah yang lebih jelas dan
mudah dipahami dibandingkan ‘urafâ sebelum Ibn ‘Arabî341. Hamzah Fansûrî
menolak sistem ittihad yang digunakan Abû Yazid al-Bistamî maupun sistem hulûl
yang digunakan Abû Mansûr al-Hallaj. Dalam pandangan Hamzah Fansûrî, kedua
sistem tersebut masih meniscayakan dualitas. Namun, penolakan tersebut bukan pada
makna ajarannya, tetapi pada sistem epistemologisnya. Namun demikian, konsepsi
ittihad dan hulûl berkonsekuensi pada keniscayaan dualitas. Paham demikian
berkonsekuensi pada terdapatnya dualitas. Ittihad dan hulûl adalah gambaran adanya
338 Izutsu, Sufism and Taoism: A Comparative Study of Key Philosophical Concepts…,
172. 339 Quraish Shihab, Menyingkap Tabir Ilahi: Asmā Al-Husnā dalam Perspektif Al-
Qurʼan (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 314. 340 Al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansûrî…, 249. 341 Abdul Hadi WM., Abdul, Hamzah Fansûrî: Risalah Tasawuf dan Puisi-Puisinya…,
21.
89
dualitas yang bersatu. Sementara Wahdah al-Wujûd benar-benar hanya menerima
satu wujûd342.
Namun demikian, tasawuf Abû Yazid al-Bistamî, Abû Mansûr al-Hallaj, ‘Ain
al-Qudhad Hamadanî pada hakikatnya merupakan bagian dari Wujudiah. Hal ini
dapat ditunjukkan melalui syatahat dan iktikad-iktikad yang mereka kemukakan.
Namun sayangnya, pada waktu itu filsafat Ibn Sînâ belum berkembang. Oleh sebab
itu, dalam membangun keilmuan dari pengalaman mistiknya, ‘urafâ masa itu belum
memiliki sistem epistemologi yang canggih. Ibn ‘Arabî adalah ‘arif pertama yang
berhasil mengembangkan epistemologi tasawuf secara sistematis dengan mengambil
sumbangan dari sistem epistemoligi Masya'iyyah Ibn Sînâ.
Hamzah Fansûrî, Ibn ‘Arabî, bersama ‘urafâ sebelumnya, seperti Abû Yazid
al-Bistamî, Abû Mansûr al-Hallaj, dan ‘Ain al-Qudhad Hamadanî adalah ‘urafâ yang
mengakui wujûd itu hanyalah satu. Sementara selainnya adalah bayangan dari satu
wujûd yakni Haqq Ta’âlâ. Memang benar bahwa masing-masing ‘urafâ tersebut
memiliki maqam yang berbeda dalam pengalaman intuitifnya. Sebagian mereka juga
menggunakan sistem epistemologi yang mengesankan adanya dualitas, namun secara
keseluruhan pemikiran, pada prinsipnya mereka adalah berpaham Wahdah al-
Wujûd343 atau Wujudiah.
7. Konsep Ta’ayyûn
Bagaimana dari yang satu memunculkan keberagaman adalah persoalan yang
telah coba dijawab sepanjang sejarah intelektual manusia. Di antara yang menarik
untuk dipertimbangkan sebagai argumentasi yang menarik adalah pemikiran
Pythagoras344. Filsuf dari Samos itu mengatakan bahwa satu atau ketunggalan
merupakan sesuatu yang tetap dan menjadi asal-usul segala sesuatu. Selanjutnya, dari
satu menghasilkan dua yang menjadi identitas alam materi. Di alam, segalanya adalah
dua atau sepasang. Sementara tiga adalah lambang ideal karena memiliki awal,
tengah, dan akhir. Empat adalah simbol bagi empat musim dan empat elemen dasar
alam. Pythagoras membuat simbol tetrakis yang menjadi simbol hubungan kesatuan
dan kemajemukan. Dalam konsep Ptyhagoras, genap adalah simbol feminim dan
ganjil adalah simbol maskulin345.
Plato mengajarkan bahwa segala kemajemukan di alam memiliki ketunggalan
di alam ideal. Konsep hubungan ketunggalan dan keberagaman yang sangat
memengaruhi pemikir muslim adalah gagasan Plotinus. Meminjam istilah Plato,
Plotinus mengatakan alam semesta berasal dari nous. Darinya muncul manifestasi
melalui sistem emanasi. Sistem itu dipakai para filosof Islam untuk memperkaya
penjelasan tentang konsep ketuhanan yang dianggap rasional346.
342 Syaifan Nur, “Kritik Terhadap Pemikiran Tasawuf Al-Raniri,”…, 137. 343 Izutsu, Sufism and Taoism: A Comparative Study of Key Philosophical Concepts…,
89. 344 Miswari, Filsafat Terakhir…, 95. 345 Bertrand Russell, History of Western Philosophy (London & New York: Routledge,
2004), 38–41. 346 Mulyadhi Kartanegara, Gerbang Kearifan: Sebuah Pengantar Filsafat Islam…, 26–
28.
90
Al-Fârâbî dan Ibn Sînâ merumuskan skema emanasi. Al-Fârâbî
menyempurnakan teori emanasi Plotinus menggambarkan Tuhan sebagai Akal Murni
yang berpikir tentang dirinya, lalu menghasilkan akal pertama. Selanjutnya, akal
pertama berpikir tentang dirinya dan Akal murni, menghasilkan akal ketiga.
Seterusnya, hingga memunculkan akal kesepuluh. Akal kesepuluh itu disebut sebagai
Malaikat Jibril atau Akal Aktif. Darinyalah muncul kemajemukan alam semesta347.
Menurut mutakallimîn, alam semesta diciptakan dari ketiadaan oleh Tuhan.
Menurut mereka, apabila alam semesta bukan berasal dari ketiadaan, berarti alam
semesta itu bersifat kekal sehingga dianggap menyamai Tuhan. Dan itu tidak
mungkin karena dalam doktrin teologis, tidak ada yang menyamai Tuhan348.
Syihab al-Dîn al-Suhrawardî mengambil jalur yang berbeda dalam
menggambarkan kejadian pluralitas alam semesta dengan menggunakan konsep
illuminasi. Menurutnya, Tuhan yang satu adalah Cahaya di atas Cahaya (Nûr al-
Anwar). Darinya memunculkan intelek-intelek abstrak (anwar al-mujarradah).
Syihab al-Dîn al-Suhrawardî menggambarkan kejadian alam sebagai pancaran
Cahaya Ilahi. Makin jauh dari sumbernya, cahaya menjadi makin redup. Sementara
alam semesta yang majemuk adalah kegelapan mutlak karena sangat jauh dengan
sumber cahaya349.
Dalam aliran Wujudiah yang digagas Ibn ‘Arabî, kemajemukan yang muncul
dari ketunggalan dijelaskan melalui sistem tajallî350. Tajallî terjadi karena Kasih
Sayang Tuhan. Dalam karyanya al-Futûhat al-Makkiyah, Ibn ‘Arabî menjelaskan
sistem tajallî secara kompleks. Pertama adalah Martabat Zat yang merupakan Misteri
Mutlak. Selanjutnya, Martabat Ahadiyah, tidak dapat dihubungkan dengan apa pun.
Selanjutnya, pada Martabat Wahidiyah sudah terkandung Martabat Nama-nama dan
Sifat-sifat, dan ‘ayân al-tsabîtah yang merupakan sumber tetap segala potensi
kemajemukan. Selanjutnya adalah ‘alam mitsal yang merupakan ‘alam khayalî atau
disebut ‘alam barzakh karena menjadi perantara antara alam ruhani dan alam materi.
Selanjutnya adalah ‘alam syahadah, yaitu alam materi yang majemuk351. Sementara
Hamzah Fansûrî menggambarkan tujuh tingkatan wujûd. Pertama, Ahadiyah, yaitu
hakikat sejati Haqq Ta’âlâ. Kedua, wahdah, yaitu hakikat Muhammad saw. Ketiga,
wahidiyah, yaitu hakikat Adam a.s. Keempat, ‘alam arwah, yaitu hakikat rûh.
Kelima, ‘alâm mitsal, yaitu hakikat bentuk. Keenam, ‘alâm ajsâm, yaitu hakikat
jasad. Ketujuh, ‘alam insân, yaitu hakikat manusia352.
347 Mulyadhi Kartanegara, Mengislamkan Nalar: Sebuah Respon Terhadap
Modernitas (Jakarta: Erlangga, 2007), 66–67. 348 Marpaung, Irwan Malik, “Alam Dalam Pandangan Abu Hamid Al-Ghazali,”
KALIMAH 12, no. 2 (September 15, 2014): 281,
http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah/article/view/240. 349 Ziai, Suhrawardi Dan Filsafat Illuminasi…, 225–227. 350 Fazeli, Mazhab Ibn ‘Arabî : Mengurai Paradoksalitas Tasybih Dan Tanzih,
Translated. (Jakarta: Sadra Press, 2016), 136. 351 Chittick, Imaginal Worlds: Ibn Al-’Arabi and the Problem of Religious Diversity…,
20–22. 352 Sri Mulyati, Tasawuf Nusantara: Rangkaian Mutiara Sufi Terkemuka (Jakarta:
Kencana, 2017), 76.
91
Dalam bab lima Syarâb, Hamzah Fansûrî menjelaskan tentang konsep lâ
ta’ayyûn dan ta’ayyûn. Konteksnya adalah dalam menjelaskan hubungan
ketunggalan dan kemajemukan, Hamzah Fansûrî menggunakan ajaran yang disebut
martabat lima. Martabat pertama adalah lâ ta’ayyûn, yaitu kunhî al-dhatî al-haqqî,
yaitu sesuatu yang sama sekali tidak dapat dijangkau.
“Maka dinamai lâ ta’ayyûn karena budi dan bichara, ilmu ma’rifat kita tiada
lulus kepadanya. Jangankan ‘ilmu dan ma’rifat kita, Anbiya’ dan Awliya’
pun hayran. Maka dinamai lâ ta’ayyûn, ya’ni ma’na lâ ta’ayyûn (itu ialah)
tiada nyata.”353
“Adapun pertama ta’ayyûn empat bahagi: ‘Ilmu dan Wujûd dan Syuhûd dan
Nûr. Ya’ni yang keempat inilah ta’ayyûn awwal, karena daripada ‘Ilmu maka
‘Alim dan Ma’lûm nyata: Kerana Wujûd maka Yang Mengadakan dan (Yang)
Dijadikan Nyata; kerana Syuhûd maka Yang Melihat dan Yang Dilihat nyata;
karana Chahaya maka Yang Menerangkan dan Yang Diterangkan nyata.
Sekalian itu daripada ta’ayyûn awwal juga. ‘Ilmu dan Ma’lûm, Awwal dan
Akhir, Zahir dan Batin beroleh nama."354
Setelah lâ ta’ayyûn, selanjutnya terjadi ta’ayyûn melalui tajallî. Pada tingkatan
itu, Dia telah menampakkan diri (tashbih) atau imanen. Ta’ayyûn (nyata) dibagi ke
dalam empat martabat atau sering disebut Martabat Empat. Pertama, ta’ayyûn awwal
yang mengandung tiga unsur, yaitu melalui wujûd, shuhûd, dan nûr. Dengan wujûd,
Dia menyaksikan (syuhûd) Diri-Nya dan Dia juga yang disaksikan oleh Diri-Nya.
Menjadi nûr sehingga Dia yang menerangi Diri-Nya355.
Ta’ayyûn tsanî adalah Dia yang diketahui, yang dilihat, yang diterangi dalam
kandungan-Nya sehingga disebut a’yan tsabitah. Disebut juga suwar ‘ilmiyyah
karena karena padanya bentuk yang dikenal. Disebut juga hakikat asya’ karena
padanya hakikat segala sesuatu. Disebut juga rûh idhafî karena dia merupakan roh
yang terpaut. Ta’ayyûn tsalits adalah rûh insanî, rûh hayawanî, dan rûh nabatî.
Ta’ayyûn rabi’ dan Ta’ayyûn khamis adalah kejadian alam semesta keseluruhannya,
termasuk jasad manusia. Kejadian ini terjadi secara terus-menerus356.
Dalam ‘Asrâr al-‘Ărifîn’, kejadian kemajemukan dari ketunggalan
digambarkan Hamzah Fansûrî dengan sangat sederhana, yakni melalui analogi-
analogi yang sangat mudah dipahami. Kemajemukan terjadi karena aktualitas Ilmu
Haqq Ta’âlâ yang memancar. Hal itu dianalogikan dengan tanah yang merupakan
sesuatu yang tunggal, namun menjelma keanekaragaman persis seperti menjelmanya
beragam perabotan, seperti kendi, buyung, periuk, tempat, dan bejana357.
353 Fansûrî, “Al-Muntahî,”…, 315. 354 Fansûrî, “Al-Muntahî,”…, 315 355 Sandigu, Wahdah al-Wujûd: Polemik Pemikiran Sufistik Antara Hamzah Fansûrî
dan Syamsuddin Sumatrani Dan Nuruddin Al-Raniri (Yogyakarta: Gama Media, 2003), 61–
62. 356 Sandigu, Wahdah al-Wujûd…, 63–64. 357 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 268.
92
Haqq Ta’âlâ yang merupakan wujûd yang satu ketika Dia sebagai 'Alim
melihat kepada 'Ilmû-Nya maka muncullah tajali pertama yang merupakan Haqîqat
Muhammad. Dalam Haqîqat Muhammad itu segala sifat terkandung. Karena semua
berasal dari Haqq Ta’âlâ, segala manifestasinya adalah kebaikan. Untuk itu, insan
yang mengandung potensi al-insân al-kâmîl dituntut untuk mengaktualisasikan
potensi sifat-sifat baik. Dengan aktualisasi kebaikan maka pada setiap entitas semesta
akan ditemukan hakikat nama dan sifat yang baik (asma' al-husna). Menjadi baik dan
buruk segala sesuatu hanya karena keterbatasan konsepsi dan interpretasi oleh
manusia358.
8. Manusia sebagai Anak Dagang
Dalam banyak bagian karyanya, Hamzah Fansûrî sangat menekankan
pentingnya melaksanakan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Jalan demikian
berguna untuk melepaskan manusia dari ketertarikan duniawi. Hal ini karena hakikat
kemerdekaan adalah lepas dari kecenderungan duniawi dan membebaskan seluruh
daya jiwa untuk berkonsentrasi pada tujuan kehidupan di muka bumi, yaitu kembali
kepada Tuhan dengan keadaan terbaik. Hamzah Fansûrî menegaskan bahwa status
kedirian manusia itu sangat bergantung kepada Tuhan. Dalam skema Wujudiah,
wujûd hanya milik Haqq Ta’ala. Selainnya, khususnya kedirian manusia, hanya
pemberian wujûd dari Haqq Ta’ala. Untuk menggambarkan kondisi manusia yang
jangankan lainnya, wujûd saja sangat bergantung kepada Haqq Ta’ala, Hamzah
Fansûrî menganalogikan kefakiran kondisi manusia sebagai anak dagang359.
Maksudnya adalah, kondisi kedirian manusia itu persis seperti pedagang yang datang
ke suatu tempat hanya untuk sementara sehingga tidak perlu melakukan banyak
urusan dan mengambil terlalu banyak karena itu akan memberatkannya dalam
melanjutkan perjalanan.
Secara ontologis, manusia sebagai mutlak kehadiran Wujûd Haqq Ta’ala
hanya perlu fokus pada perkembangan jiwanya dalam berbagai stasiun perjalanan.
Alam dunia hanya bagian dari perjalanan jiwa manusia persis seperti pedagang yang
hanya tinggal di suatu pelabuhan. Mau tidak mau, harus melanjutkan perjalanannya.
Analogi anak dagang dalam menggambarkan kondisi manusia digunakan Hamzah
Fansûrî karena pada masa itu perkembangan kebudayaan dan diskursus keilmuan
berkembang pesat di pantai pelabuhan. Tentunya, masyarakat sangat akrab dengan
kondisi pedagang sehingga analogi tersebut menjadi sangat efektif karena dapat
mudah dipahami masyarakat.
Anak dagang dalam masyarakat Melayu dimaknai untuk seorang santri yang
pergi menuntut ilmu ke pondok. Perjalanan anak dagang dalam makna ini adalah
untuk mengambil perbekalan, yakni ilmu untuk memudahkan jalan mereka dalam
menjalani hidup dan mempersiapkan bekal amal untuk akhirat. Hamzah Fansûrî juga
menggunakan kiasan anak jamu. Hal ini karena seorang jamu (tamu) datang ke suatu
tempat tidak untuk berlama-lama. Datang hanya sejenak, menuntaskan urusan, lalu
358 Teuku Safir Iskandar Wijaya, Falsafah Kalam (Lhokseumawe: Nadiya Foundation,
2003), 78. 359 Abdul Hadi WM, Tasawuf Yang Tertindas: Kajian Hermeunetik Terhadap Karya
Hamzah Fansuri, 245.
93
segera kembali. Tentunya demikian juga tujuan hidup manusia di dunia, tidak boleh
terikat dengan kecenderungan duniawi360.
Manusia harus selalu sadar akan kefakiran dirinya di hadapan Tuhan sehingga
fokusnya hanya mencapai keridaan Allah. Bila tidak, manusia itu mengingkari
hakikat dirinya. Tentang bahaya kecenderungan duniawi, Hamzah Fansûrî
menggambarkan:
Berahimu da'im akan orang kaya
Manakan dapat tiada berbahaya
Ajib sekali hati sahaya
Hendak berdekap dengan Mulia Raya
Kesadaran akan kefakiran diri insan adalah hakikat tauhid. Disadari bahwa
kedirian itu sama sekali tidak memiliki eksistensi. Keberadaan manusia sepenuhnya
adalah kehadiran wujûd dari Haqq Ta’ala. Kesadaran seperti ini oleh Hamzah Fansûrî
digambarkan dengan laron atau kaluh-kaluh yang dengan sukarela terbang menuju
api untuk melenyapkan diri.
Anak dagang sebagai gambaran kefakiran manusia menunjukkan kesamaan
derajat manusia atas sesamanya. Manusia hanya perlu tunduk kepada Allah karena
padanya saja seluruh makhluk bergantung. Abdul Hadi WM mengatakan, kesadaran
akan kefakiran diri manusia yang digambarkan Hamzah Fansûrî tidak digambarkan
dengan sikap sentimental, mengiba, dan penuh linangan air mata361. Kondisi ini oleh
Hamzah Fansûrî malah digambarkan sebagai keberanian, kekuatan, dan semangat
hidup yang berapi-api362. Hamzah Fansûrî sangat sadar bahwa:
Hidup dalam dunya umpama dagang
Datang mawsim kita 'kan pulang
Lâ tasta khiruna sa'atan lagi kan datang
Mencari ma'rifat Allah jangan kita alang-alang363
Mencari ma'rifat Allah, yakni mengenal Allah yang telah melampaui ‘ilm
yaqin, ‘ain yaqin, dan haqq al-yaqin yang diperoleh setelah syariat, tarekat, dan
hakikat. Pengenalan inilah yang diinginkan supaya insan dapat bermain mata dengan
Rabb al-'alam. Kondisi ini seperti Simurgh dalam gambaran Farîd al-Dîn Attâr dalam
“Mantiqut Tayr”. Simurgh adalah personifikasi jiwa manusia yang telah mencapai
singgasana Ilahi. Simurg inilah yang dicari oleh burung-burung dalam gambaran
Farîd al-Dîn Attâr yang menamsilkan jiwa pesuluk364.
Braginsky mengatakan, “Syair Burung Pinggai” yang digubah Hamzah
Fansûrî tidak terlepas dari semangat “Mantiqut Tayr” karya Farîd al-Dîn Attâr.
360 Hamzah Fansuri, “Syair Perahu,” dalam Seulawah: Antologi Sastra Aceh, ed. L.K.
Ara, Taufiq Ismail, and Hasyim KS (Jakarta: Yayasan Nusantara, 1995), 3–4. 361 Hadi, Tasawuf Yang Tertindas…, 250. 362 Hadi, Tasawuf Yang Tertindas…, 250. 363 Hadi, Tasawuf Yang Tertindas…, 251. 364 Miswari, Tasawuf Terakhir…, 126–127.
94
Dalam penafsiran Braginsky, Simurg dalam konteks Hamzah Fansûrî adalah Burung
Pinggai. Bila dalam pemaknaan Farîd al-Dîn Attâr bahwa Simurgh adalah Tuhan,
sementara dalam pemaknaan Hamzah Fansûrî, Simurgh adalah Nur Muhammad365.
'Ilm al-yaqin nama ilmunya
'Ayn al-yaqin hasil tahunya
Haqq al-yaqin akan lakunya
Muhammad Nabi asal gurunya366
Hamzah Fansûrî juga mengganti istilah anak dagang dengan istilah anak
Adam. Dalam konteks ini, manusia digambarkan sebagai khalifah Allah di muka
bumi. Bila melenyapkan dirinya di hadapan Allah, manusia yang berpotensi
menyerap seluruh Nama dan Sifat Tuhan dapat mengaktualisasikan sifat-sifat
tersebut. Sebagai khalifah, manusia memikul amanat yang sanga besar. Amanat ini,
bahkan enggan dipikul oleh gunung sekalipun (QS. 33: 72).
Manusia itu terasing dari dunia ini. Manusia sejatinya adalah makhluk rohani.
Manusia memiliki potensi luar biasa untuk mengembangkan wujûd-nya hingga dapat
menyatu dengan Allah. Syaratnya manusia harus menjauhkan diri dari
kecenderungan duniawi, bersikap zuhud, dan melakukan penyucian diri sehingga
hatinya menjadi wadah manifestasi Ilahi.
Aho segala kita yang äsyiqî
Ingat-ingat akan makna insåni
Jika sungguh engkau bangsa rúhani
Jadikan dirimu rupa Sulthâni
Kenal dirımu hai anak alim
Supaya engkau nentiasa sálim
Dengan dırımu yogya kau qá im
Itulah haqiqat salat dan sháim
Dirimu itu bernama khalil
Tiada bercerai dengan Rabb al-Jalil
Jika dapat ma'na dirimu akan dalil
Tiada berguna mazhab dan sabil
Kulluman 'alayhâ fârnin áyat min Rabbihi
Menyatakan ma'na irji îilå ashliki
Akan insan yang beroleh tarwfiqihi
Supaya karam di dalam sirru sirrihi
Situlah wujûd sekalian fanun
Tanggallah engkau dari mäl wal al banun
365 Braginsky, Yang Indah, Berfaedah Dan Kamal…, 508–510. 366 Hadi, Tasawuf Yang Tertindas…, 253.
95
Engkaulah asyiq terlalu junun
Inna lillahi wa inna ilayhi ruji’un367
Segala yang asyiqî, yakni yang menempuh jalan spiritual, mereka yang sadar
bahwa wujûd dirinya dan segenap alam adalah manifestasi cinta Ilahi, dihimbau
untuk mengeksplorasi hakikat kediriannya. Dengan begitu disadari bahwa dirinya
merupakan bangsa rohani. Dengan demikian, segala tindakan kedirian haruslah
berdasarkan rupa sultanî, yakni menjadi sarana aktualisasi Nama dan Sifat Ilahi368.
Dalam penjelasan Braginsky, al-Rahman dalam ontologi syair sufi Melayu
identik dengan penciptaan. Dalam menjelaskan Asrâr karya Hamzah Fansûrî,
Braginsky mengatakan bahwa dalam pandangan Hamzah Fansûrî, alam semesta
memperoleh wujûd dari Rahman. Dalam skema Martabat Tujuh, Martabat pertama
adalah “Dia” (Huwâ) yang sama sekali tidak terjangkau, tidak dikenal. Pada Martabat
Kedua dikenal dengan “Allah”, yaitu Wahdah. Pada Martabat ketiga, yakni Rahman
yang disebut Martabat Wahidiyah. Dalam Rahman itulah sumber segala wujûd
menemukan potensi parsialitasnya. Sementara dalam Rahîm itu adalah sumber nama
segala yang indah. Melalui skema inilah para penyair suka memulai karyanya dengan
tiga nama dalam martabat, yaitu Bismî Allah al-Rahman al-Rahîm. Hal ini karena
puisi merupakan gambaran keindahan. Puisi Melayu yang bercorak sufistik dianggap
sebagai manifestasi keindahan Ilahi369.
Shams al-Dîn al-Sumatranî mengatakan, ''Maka hakikat diri Anda pada kedua
martabat ini (yakni sebagai potensialitas dan aktualitas) adalah hakikat diri Allah.
“Wujûd Tuhan itu diwarnai dengan hukum-hukum dan efek-efek ...''. Dalam
menjelaskan pernyataan ini, Abdul Aziz Dahlan mengatakan pernyataan tersebut
harus dipahami bahwa maksud Shams al-Dîn al-Sumatranî adalah wujûd insan adalah
wujûd yang dipancarkan oleh Tuhan370. Hal ini karena memang dalam irfân,
eksistensi alam adalah tajallî Ilahi371.
Wujûd Tuhan sebagai eksistensi alam dalam penjelasan Shams al-Dîn al-
Sumatranî diwarnai dengan hukum-hukum dan efek-efek. Oleh sebab itu, wujûd alam
tidak dapat secara langsung disamakan dengan wujûd Tuhan karena wujûd pada alam
itu adalah manifestasi, adalah merupakan bagian dari tanzih, bukan semata tasybih372.
Dalam gambaran filsafat, wujûd alam adalah wujûd mujarrâd, yakni wujûd yang telah
bercampur dengan mâhiyâh373. Kasih Tuhan adalah manusia itu sendiri sehingga
dengan limpahan kasih, manusia berpeluang menjadi ‘urafâ, yakni sebagai wadah
manifestasi cinta secara keseluruhan sehingga alam dapat menjadi cermin Tuhan.
367 Hadi, Tasawuf Yang Tertindas…, 263. 368 Hamid Parsania, Existence and the Fall: Spiritual Anthropology of Islam,
(London: ICAS, 2006), 115–116. 369 Braginsky, Yang Indah, Berfaedah, dan Kamal…, 164. 370 Abdul Aziz Dahlan, Penilaian Mutakallimînis atas Paham Wahdatul Wujud
Dalam Tasawuf Syamsuddin Sumatrani (Padang: IAIN Imam Bonjol Press, 1992), 142. 371 Sandigu, Wahdatul Wujud:… 62–64. 372 Fazeli, Mazhab Ibn Arabi:…, 174–175. 373 Nasr, Islamic Philosophy From Its Origin to the Present…, 63–64.
96
Meraih maqâm ‘urafâ adalah proses aktualisasi wujûd. Jalan menuju ma’rifat itu
sangat rumit. Pesuluk harus mampu meraihnya374.
Bismillah al-Hayy al-Baqi
Yaitu Mahbub yang maha ‘alî
Rupanya terlalu shafî
Lingkup dengan 'alam tiada Ia khalî
Mahbub itu terlalu nyata
Akan orang yang mendapat kata
Jika sungguh engkau bermata
Lihat mahbub-mu itu rata-rata
Mahbub itu terlalu bijak
Dindingnya emas dan perak
Perlahan-lahan pergi ke hempenak
Supaya dapat mahbub-mu jinak375
Pada Haqq itulah 'Ilmû bergantung. Yang Hidup Sejati adalah Dia sehingga
'Alîm sejati hanya Dia. Karena itu, sufi mengaku dalam fânâ, sebagai bagian dari
perjalanan spiritual menuju ma’rifat, mengaku tidak memiliki pengetahuan karena
pengetahuan hanya Dia. Allah itu terlalu suci (shafî), yakni tiada apa pun bersama-
Nya. Sementara Dia itu lingkup dengan alam tidak khalî, yakni benar-benar hadir
sehingga alam adalah kehadiran-Nya secara mutlak. Sementara alam dikatakan
sebagai tanda kehadiran-Nya. Maka dari itu, tanda kehadiran itu hanya dapat
disingkap oleh yang telah memperoleh ma’rifat, yakni pengetahuan tertinggi yang
menafikan perantara subjek dan objek pengetahuan. Adapun pengetahuan sejati
adalah Dia semata. Nabi Muhammad mengaku tidak benar-benar kenal akan Allah.
Sementara yang paling mengenal Allah adalah Dia sendiri. Sementara Nabi
Muhammad telah memperoleh ma’rifat tertinggi376.
Allah yang tidak dapat dijangkau itu oleh Hamzah Fansûrî disebut lâ ta’ayûn.
Pada posisi itu, ‘urafâ dan para nabi juga tidak dapat menjangkau. Analogi yang
dibuat untuk kondisi itu adalah bahr al-amîq. Tidak ada siapa pun yang berhasil
menyelam ke sana. Abdul Hadi WM mengatakan, ''Orang yang telah ma’rifat dapat
menyaksikan Kekasih di mana saja''377. Sementara ma’rifat atau pengetahuan sejati
itu hanya milik Allah. Pengetahuan Tuhan itu tiada berhingga. Sementara hijab untuk
memperoleh ma’rifat adalah hasrat duniawi yang disimbolkan dengan emas dan
perak. Untuk mengatasi hijab itu, pesuluk harus tetap pada perintah Allah,
melenyapkan ego, dan beradab sopan. Proses yang perlu dilalui untuk mencapai
ma’rifat itu adalah dengan adab dan ilmu yang dituntut secara sabar dan konsisten
374 Yazdi, The Principles of Epistemology in Islamic Phlosophy: Knowledge by
Presence…, 19. 375 Abdul Hadi WM, Tasawuf Yang Tertindas…, 266–268. 376 Al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansuri…, 271. 377 Abdul Hadi WM, Tasawuf yang Tertindas…, 268.
97
kepada ahli ma’rifat. Shams al-Dîn al-Sumatranî menjelaskan, bila tertarik dengan
dunia, kekasih sejati menjadi jauh, sulit menjadi ahlullah, tidak akan wasil dengan
Allah, dan tidak akan mencapai musyahadah sempurna378.
Manusia terlalu sibuk dengan kecenderungan duniawi sehingga jalan menuju
ma’rifat menjadi sukar. Banyak manusia teperdaya dengan bujukan hawa nafsu
sehingga untuk memperoleh ma’rifat menjadi manikam di mulut ular, begitu sulit
mendapatkannya. Padahal, manusia sebagai ahsînî takwîm memiliki potensi
penyempurnaan wujûd yang tidak terbatas. Potensi itu memberikan peluang kepada
manusia memperoleh ma’rifat melalui jalan suluk dengan sarana seperti
suluk. Dalam suluk diajarkan latihan merantai hawa nafsu, mempelajari jalan wasil
akan Allah, melatih kecenderungan hati hanya kepada Allah sehingga dapat menjadi
kekasih Allah379.
Hamzah Fansûrî mengatakan bahwa hati manusia memiliki kemampuan untuk
didayagunakan dalam rangka wasil dengan Allah. Dalam analoginya, Hamzah
Fansûrî menggambarkan hati sebagai Ka’bah dan unggas quddusî. Dua analogi itu
untuk menggambarkan bahwa hati merupakan singgasana Ilahi. Di dalam hati
terkandung air hayat yang maksudnya adalah hati manusia mengandung sumber
pengetahuan utama, yakni tauhid. Gambaran orang yang meminum air hayat
maksudnya adalah pesuluk yang berhasil memperoleh ilmu ma’rifât380.
C. Analogi Kontekstual Wujudiah Hamzah Fansûrî
Meskipun terkesan tradisional, bukan berarti tempat Hamzah Fansûrî berkarier
dan menyebarkan gagasannya terisolasi. Bahkan, Fansur adalah sebuah kota dagang
yang sangat maju pada masa itu. Keramaian Fansur pada masa itu hanya dapat
disamakan dengan Singapura hari ini. Singapura menjadi sangat maju karena menjadi
destinasi dan transit para pedagang lintas benua. Demikian juga Fansur adalah sebuah
kota yang sangat ramai. Kota tersebut adalah salah satu destinasi utama dan tempat
transit terpenting di Selat Malaka381.
Sejarah pertempuran antarnegara dari masa ke masa di Semenanjung Malaya,
yang hari ini diungguli Britania dalam bentuk Singapura, adalah sejarah
memperebutkan destinasi perdagangan dan transit utama kapal-kapal lintas benua.
Kapal-Kapal dari Eropa, India, Timur Tengah, Afrika, dan sebagainya yang hendak
menuju Cina, Filipina, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Maluku, Thailand, dan
sebagainya dan sebaliknya, harus melakukan transit di Semenanjung Malaka. Sejarah
kejayaan kerajaan-kerajaan di sepanjang pantang Selat Malaka adalah sejarah
keberhasilan menarik wilayahnya menjadi destinasi dan transit utama pelayaran Selat
Malaka382.
378 Hasjmy, Ruba’i Hamzah Fansuri…, 38. 379 Hasjmy, Ruba’i Hamzah Fansuri…, 37–38. 380 Hadi, Tas Abdul Hadi WM, Tasawuf yang Tertindas…, 288. 381 Guillot, dan Ludvik Kalus, Enskripsi Islam Tertua di Indonesia (Jakarta: Gramedia,
2008), 85. 382 Askandar, Jiwa Bahari Sebagai Warisan Nenek Moyang Bangsa Indonesia
(Jakarta: Biro Sejarah Maritim AL, 1973), 164.
98
Sejarah maju dan surutnya kerajaan-kerajaan di Semenanjung Malaka silih
berganti. Sejarah mencatat kemajuan pernah dialami Kerajaan Lamuri, Kerajaan
Jeumpa, lalu beralih ke Kesultanan Peureulak, lalu ke Samudra Pasai, lalu ke Aceh
Darussalam, lalu ke Malaka, dan Aru. Terdapat kemungkinan hubungan Timur
Tengah ke Cina dilalui melalui pantai selatan Pulau Sumatra melalui Selat Sunda
untuk menghindari lanun Melayu yang ganas sehingga pantai selatan Sumatra
menjadi alternatif.383.
Pada masa Hamzah Fansûrî lahir dan dibesarkan, negeri-negeri Melayu sedang
mengalami masa kemunduran akibat serangan Majapahit dan Portugis384. Pada masa-
masa tragis, Hamzah Fansûrî pergi mengembara untuk berdagang dan menuntut ilmu
di Singkil dan bertolak ke Timur Tengah. Sekembalinya dari Timur Tengah, Hamzah
Fansûrî berkarier di Fansur. Saat itu, sultan dan pengusaha berhasil menjadikan
wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam sebagai destinasi dan transit
dagang385.
Syed Muhammad Naquib Al-Attas386 benar ketika mengatakan bahwa Hamzah
Fansûrî lahir di Syahr Nawi. Akan tetapi, Syahr Nawi yang dimaksud itu bukan
berarti Persia dan belum tentu juga adalah Thailand. Hal ini karena dengan tegas
Hamzah Fansûrî mengatakan: “Hamzah Syahr Nawi zahirnya jawi”. Jadi, Syahr
Nawi itu adalah di negari Melayu yang disebut Jawi. Syahr Nawi juga belum tentu
merupakan istilah simbolis sebagai sebuah perjalanan spiritual sebagaimana
kecenderungan Drewes dan Brakel387. Pandangan Syed Muhammad Naquib Al-Attas
bahwa bahwa Syahr Nawi itu bukan simbolisme, melainkan bermakna literal sebagai
tempat kelahiran Hamzah Fansûrî. Pada masa itu, perguruan agama yang besar hanya
ada di Pasai sebelum selanjutnya berkembang di Singkil dan Kutaraja388. Dengan
demikian, terdapat kemungkinan Syahr Nawi itu adalah Pasai.
Terdapat kemungkinan Syahr Nawi adalah negeri yang ditahbiskan kepada
nama Syahri Nawi, yaitu putranya Syahriansyah Salman yang menyebarkan Islam ke
Peureulak yang disebut juga dengan negeri Samudra389. Ketika negeri Samudra
disatukan dengan negeri Pasai, lokasi Syahri Nawi meliputi negeri Samudra dan
negeri Pasai. Sebelum Hamzah Fansûrî lahir, negeri Samudra dan negeri Pasai
memang telah disatukan oleh Malik Al-Saleh390.
383 Daniel Perret, Sejarah Johor-Riau-Lingga Sehingga 1914: Sebuah Esei Bibliografi
(Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Pelancongan Malaysia, 1998), 410. 384 Said, Aceh Sepanjang Abad Vol. I, 101. 385 Ali Hasjmy, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia (Medan:
Pustaka Al-Ma’arif, 1981), 13. 386 Al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansûrî,… 10. 387 Drewes dan Brakel, The Poems of Ḥamzah Fansûrî…, 5. 388 Perguruan Islam tertua di Asia Tenggarah adalah Cot Kala, lalu Blang Pria di Pasai,
setelah itu peruan Islam berpindah ke Singkil dan Kutaraja. Lihat, Hasjmy, Bunga Rampai
Revolusi Dari Tanah Aceh (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 57–59. 389 Abdul Hadi WM mengatakan, menurut Hasan Muarif Ambary, Syahr Nawi adalah
Peureulak. Lihat, Abdul Hadi WM., Tasawuf Yang Tertindas…, 142 Namun istilah tanah
Syahri Nawi diperluas hingga pasai ketika Samudra disatukan dengan Pasai. 390 Hasjmy…, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia…, 153–154;
Pocut Haslinda Muda Dalam Azwar, Silsilah Raja-Raja Islam di Aceh: Hubungannya dengan
99
Hamzah Nin asalnya Fansuri
Mendapat wujûd di Tanah Syahr Nawi391
Lakab “Fansuri” maksudnya adalah tempat Hamzah Fansûrî berkarier setelah
pulang mengembara dari Timur Tengah. Hamzah Fansûrî telah menuntut ilmu dan
kemungkinan berdagang di Hijaz, Irak, Palestina, dan Persia392.
Hamzah Fansûrî di dalam Mekkah
Mencari Tuhan di Bayt Al-Ka’bah
Dari Barus ke Kudus terlalu Payah
Akhirnya mendapat di dalam rumah393
Terdapat kemungkinan Hamzah Fansûrî lahir dan besar di Pasai dan menuntut
ilmu di dayah Blang Pria. Dari Pasai Hamzah Fansûrî bertolak ke Singkil. Dari
Singkil Hamzah Fansûrî bertolak ke Palestina melalui Barus. Dalam hal ini, “Barus”
dan “Fansur” berpeluang memiliki perbedaan. Barus adalah tempat Hamzah bertolak
dari Singkil. Pelabuhan terdekat dari Singkil waktu itu mungkin adalah Barus.
Sementara Fansur adalah tempat Hamzah Fansûrî berkarier setelah pulang dari
pengembaraannya394.
Hamzah Gharib unggas Quddusi
Akan rumahnya Bayt al-Ma’muri
Kursinya sekalian kapuri
Di Negeri Fansuri min al-asyjari395
Bait di atas menunjukkan bahwa Hamzah tinggal di Fansur, tetapi sebenarnya
dia bukan berasal dari daerah itu. Fansur itu berada di Bayt al-Ma’muri, yakni nama
lain dari Kesultanan Aceh Darussalam. Adapun Kesultanan Aceh Darussalam adalah
pemangku monopoli kekayaan alam, termasuk kapur barus yang umumnya
didapatkan antara Singkil dan Tapanuli yang pada masa tersebut kawasan-kawasan
itu masuk kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Maka dari itu, meskipun pada
masa itu terdapat kemungkinan pelabuhan Barus masih aktif, titik tolak ekspor ke
Raja-Raja Melayu Nusantara (Jakarta: Yayasan Tun Sri Lanang, tt.), 62; Nasution dan
Miswari, “Rekonstruksi Identitas Konflik Kesultanan Peureulak,” 168–181. 391 Al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansûrî…, 7 Bandingkan, ; Drewes dan Brakel,
The Poems of Ḥamzah Fansûrî, 5. Lihat juga, ; Abdul Hadi WM, Tasawuf Yang
Tertindas…,140. 392 Al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansûrî, 10–11. 393 Abdul Hadi WM., Tasawuf Yang Tertindas…, 139. 394 Ichwan Azhari mengatakan bahwa Fansur adalah Lhok Pancu atau lebih dikenal
Ujong Pancu, salah satu desa di Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar, tidak jauh dari pusat
Kesultanan Aceh Darussalam. Lihat, Ichwan Azhari, Kapur Dari Barus: Islam dan Jaringan
Perdagangan Kuno, (Medan, 2019), 1–12. 395 Al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansûrî, 6, Bandingkan, Drewes dan Brakel,
The Poems of Ḥamzah Fansûrî.., 74.
100
negeri-negeri yang jauh adalah melalui Fansur. Bahkan pada masa itu, begitu
besarnya pengaruh Kesultanan Aceh Darussalam396, tidak tertutup kemungkinan
bahwa pelabuhan-pelabuhan di Tamiang, Barus, Meulaboh, Labuhan Haji, Pasai, dan
Panteraja mengirim hasil bumi ke Fansur untuk diekspor397.
Drewes dan Brakel mengatakan bahwa Dari Barus ke Kudus terlalu payah
adalah bukti bahwa Hamzah Fansûrî pernah melakukan perjalanan ke Kudus di Pulau
Jawa398. Braginsky juga berpandangan tidak jauh berbeda. Akan tetapi, A.H. John
punya pemaknaan yang lebih imajinatif. Menurutnya, Kudus yang dimaksud bukan
Kudus di Pulau Jawa, tetapi di Baitulmaqdis, Palestina. Bahkan menurutnya, frasa
tersebut bukan berarti Hamzah Fansûrî harus ke Palestina, melainkan hanya
menggambarkan berjalan dari Barus ke Kudus adalah sia-sia karena Tuhan bisa
ditemukan “di dalam rumah”399.
Hamzah Fansûrî juga menggunakan istilah “Barus” dan “Fansuri” dengan
berbeda sehingga memungkinkan Barus dan Fansur itu tidak sama. Kalau sama, akan
disebutkan satu istilah saja. Adapun Fansur adalah tempat transit favorit kapal-kapal
yang berlabuh antara Cina dan Timur Tengah. Kapal-kapal melewati antara Pulau
Weh dan Pulau Breuh-Pulau Nasi untuk bersandar: berdagang dan mengisi
perbekalan. Maka dari itu, terdapat kemungkinan titik lokasi perdagangan
kosmopolitan adalah Ujong Pancu hingga Ulee Lhee yang sekarang telah sangat
banyak terkikis. Pada masa dahulu, kemungkinan di sanalah letak bandar terbesar di
Nusantara. Orang-orang dari Timur Tengah menyebutnya Fansuri atau Fansuria400.
Sebelumnya, dari Ujong Pancu hingga Ujong Batee Aceh Besar berbentuk tanjung.
Karena tsunami hingga puluhan meter terjadi berulang kali dalam tempo beberapa
ratus tahun sekali, sekarang bentuknya menjadi teluk. Ujong Pancu yang dikenal
dengan Fansur yang dahulunya pernah menjadi destinasi dan transit terpenting Jalur
Sutra, kini tenggelam ke dalam lautan beserta sejarahnya401. Pernyataan bahwa
Fansur adalah dari kata “pancu” menjawab kebingungan kenapa ada makam
(makamnya Muazzam Shah) di Barus, tetapi ditera tulisan, min balad al-Fansur (dari
396 Amirul Hadi, “Islam and State in Sumatra: A Study of Seventeenth-Century Aceh
a Study of Seventeenth-Century Aceh (Islamic History and Civilization)” (Mc.Gill
University, 1999), 18-24. 397 Denys Lombard, Kerajaan Aceh …, 123. 398 Drewes dan Brakel, The Poems of Ḥamzah Fansûrî…, 10. 399 A.H. Johns, “The Poems of Hamzah Fansûrî,” Bijdragen tot de taal-, land- en
volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia 146, no. 2
(January 1, 1990), 326. 400 Hal itu disampaikan oleh Ichwan Azhari dalam presentasinya. Makalah lihat,
Azhari, Kapur Dari Barus: Islam Dan Jaringan Perdagangan Kuno, 1–12. 401 Hal ini dikuatkan dengan temuan-temuan banyak makam kuno di Gampong Pande
Banda Aceh yang tidak jauh dari Ujong Pancu. Sehingga sangat besar kemungkinan abrasi
dari bandar lama Ujong Pancu hingga sebagian Gampong Pande yang sudah tenggelam. Lihat,
Mondza, “Rekaman Tsunami di Gua Ek Leuti,” Tempo, last modified 2019, accessed February
6, 2020, https://majalah.tempo.co/read/ilmu-dan-teknologi/158346/rekaman-tsunami-di-gua-
ek-leuntie; Koestoro, Lucas Partanda, “Gampong Pande, Situs Penting Di Ujung Utara Pulau
Sumatera.” Berkala Arkeologi SANGKHAKALA 19, no. 2 (May 21, 2017): 75.
http://sangkhakala.kemdikbud.go.id/index.php/SBA/article/view/27 .
101
negeri Fansur). Hal ini hanya bisa dijawab dengan akurat bila menerima Barus itu
bukan Fansur. Pengucapan barus menjadi fansur juga sangat jauh bunyinya. Zakaria
Ahmad402, Mohammad Said403, dan A. Hasjmy404 sepakat bahwa Barus itu berbeda
dengan Fansur405.
Fansur adalah sebuah kota dagang dan kota pelabuhan yang sangat padat dan
telah lama menjalin hubungan dengan berbagai bangsa di dunia, seperti Cina, India,
Persia, Arab, dan Eropa. Fansur tidak selalu menjadi bandar terbesar sepanjang masa.
Sebelum Fansur, Pasai telah menjadi bandar terbesar. Sebelum Pasai, Lamuri telah
menjadi bandar terbesar. Kemajuan Fansur terjadi pada abad ke-14 hingga abad ke-
16. Pada masa itulah Hamzah Fansûrî berkarier dalam Kesultanan Aceh
Darussalam406. Melalui eksplorasi dokumen-dokumen dari berbagai sumber, Denys
Lombard menunjukkan bahwa sebenarnya kondisi Kesultanan Aceh Darussalam
sangat buruk. Seorang raja dilantik dan diturunkan ditentukan oleh kecenderungan
orang-orang kaya atau pengusaha di sana407. Sebagai salah satu kota dan pelabuhan
tersibuk, Aceh Darussalam yang berpusat di Kutaraja yang meliputi Fansur adalah
tempat perputaran ekonomi yang sangat besar408. Proses perputaran ekonomi raksasa
itu dikendalikan para pengusaha. Regulasi-regulasi sosial ekonomi ditentukan
melalui jalur politik yang pada masa itu dimainkan melalui peraturan adat. Penguasa
adat adalah sultan. Untuk itu, para pengusaha sangat berkepentingan dengan sultan.
Pengusaha bersedia memberikan upeti yang besar kepada sultan bila mendukung dan
mempermudah regulasi. Sebaliknya, konspirasi dilakukan dengan menggulingkan
(tetapi lebih sering dibunuh) apabila menghambat regulasi bagi pengusaha409.
Begitu besarnya ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam waktu itu sehingga
sebuah dokumen berbahasa Portugal sebagaimana dilampirkan dan diterjemahkan
oleh Lombard melaporkan, “... penduduknya padat hingga orang hampir tak bisa
lewat di jalan."410 Dengan demikian, perputaran uang terjadi dalam jumlah yang
sangat besar. Semua itu berada di bawah kendali para pengusaha. Di dunia tidak ada
yang lebih berkuasa dan menentukan kekuasaan, selain uang. Setidaknya begitulah
yang menjadi prinsip para pengusaha di sana. Mereka mengadakan pertemuan untuk
402 Ahmad, Zakaria, Sekitar Keradjaan Atjeh dalam Tahun 1520-1675 (Medan:
Monoro, 1972), 110–111. 403 Said, Aceh Sepanjang Abad Vol. I, 413. 404 Hasjmy, Ali, Ruba’i Hamzah Fansûrî (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,
1976), 11. 405 Namun menurut Azhari itu kurang tepat karena sebenarnya yang lebih meyakinkan
adalah, Fansur yang dimaksud merupakan Ujong Pancu. Lihat, Azhari, Kapur dari Barus:
Islam dan Jaringan Perdagangan Kuno, 1–12. 406 Azra, Jaringan Ulama…, 206–207. 407 Lombard, Kerajaan Aceh…, 227. 408 Posisi Fansur sebagai kawasan bandar pelabuhan bagi Kutaraja dapat dianalogikan
seperti Belawan dan KIM bagi Medan. Tentang KIM, lihat, Tina Hadiyanti, “Majalah IM
Indonesia : Pemimpin Pembawa Perubahan 2018,” Majalah IM Indonesia (Jakarta, 2018), 29. 409 Lombard, Kerajaan Aceh …, 226–227. 410 Lombard, Kerajaan Aceh …,, 226.
102
mendukung atau melengserkan seorang sultan. Itu mereka lakukan semata-mata
untuk kelancaran perniagaan mereka411.
Dalam konteks masyarakat yang pada bagian pesisirnya sangat kosmopolit dan
masyarakat pedalamannya mempertahankan tradisi-tradisi itulah, Hamzah Fansûrî
menyebarkan ajarannya. Dalam hal ini, di antara pengaruh kontes sosiokultural yang
sangat memengaruhi adalah tentang pesan Hamzah Fansûrî untuk terlena dengan
kemewahan dunia, dan menggunakan analogi-analogi yang kontekstual dalam
menyebarkan ajarannya. Analogi-analogi dimaksud adalah objek-objek yang dekat
dengan masyarakatnya sehingga mudah dipahami, seperti analogi tanah dan
perabotan, matahari dan sinarnya, kayu dan buah catur, laut dan ombak, dan
sebagainya.
6. Tanah dan Perabotan Rumah Tangga sebagai Wujûd Mendasar
Mengenai analogi tanah dan perabotan, Hamzah Fansûrî menulis:
“Ya’ni seperti tanah; dijadikannya berbagai-bagai akan dia; adakan buyung,
adakan periuk, asal tanah sebangsa hukumnya. Berbagai-bagai bejana itu
beroleh dan peri daripada tanah juga. Akan alampun demikian lagi;
sungguhpun berbagai-bagai asalnya daripada Chahaya itu juga.”412
Konteks analogi yang dikutip di atas berada dalam dalam konteks penjelasan
tentang sifat ‘Alim Haqq Ta’âlâ, yang mana dari ‘Ilmu Haqq Ta’aala muncul aneka
ragam realitas. Analoginya adalah seperti tanah. Wujûd Allah diumpamakan seperti
“tanah” dan wujûd makhlûqat (wujûd selain Al-Haqq), seperti buyung, periuk, dan
bejana. Maksudnya adalah, semua wujûd makhlûqat adalah satu wujûd dengan Wujûd
Al-Haqq. Menjadi kendi, periuk, buyung, dan tempat adalah namanya saja. Sejatinya
adalah tanah. Pada keseluruhan buyung, periuk, dan bejana keseluruhannya adalah
tanah. Demikianlah segala wujûd makhlûqat adalah dari Wujûd al-Haqq sekalipun
beragam rupa dan namanya413.
“Seperti tanah; diperbuat kendi, atau periuk, atau buyung, atau tempat. Tanah
itulah asal wujûd sekalian bejana itu. Jika tiada tanah itu, dimana kendi dan
periuk akan beroleh wujûd?”414
Sebagaimana kutipan di atas, Hamzah Fansûrî menganalogikan Kesatuan
Wujûd antara Bâsîth dengan segenap makhlûqat sebagaimana wujûd itu satu seperti
tanah, menjadi beragam makhlûqat seperti menjadi beragam benda, seperti kendi,
buyung, periuk, tempat, dan bejana sebagaimana beragam makhlûqat yang asal
wujûd-nya adalah satu.
Hamzah Fansûrî juga menjelaskan bahwa dalam pandangan mutakallimîn,
antara wujûd Bâsîth dengan wujûd beragam perabotan itu berbeda. Para mutakallimîn
411 Lombard, Kerajaan Aceh …, 226–227. 412 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 259. 413 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 268. 414 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 268.
103
berpandangan bahwa Wujûd Haqq Ta’ala dengan wujûd makhlûqat itu berbeda.
Sementara bagi Hamzah Fansûrî dan para ‘urafâ lainnya, melihat wujûd Bâsîth dan
wujûd makhlûqat itu sama. Karena bila berbeda, berkonsekuensi pada terbatasnya
Wujûd Haqq Ta’âlâ 415.
Pada kariernya di Kesultanan Aceh Darussalam tepatnya di Fansur maka
Samudra Pasai, Singkil, dan Fansur adalah lokus lingkungan Hamzah Fansûrî.
Sementara di antara tiga daerah tersebut, Fansur menjadi lingkungan ideal Hamzah
Fansûrî dalam mengimajinasikan sasaran ajarannya. Dengan demikian, dalam
merumuskan konsep ajaran, termasuk dalam memilih diksi dan menetukan objek-
objek analogi yang dibuat untuk mengomunikasikan ajarannya, Fansur menjadi
imajinasi utama sasaran Hamzah Fansûrî dalam mengomunikasikan ajarannya.
Fansur khususnya, dan seluruh wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam,
pada sekitar abad ke-15, menciptakan perabotan dari tanah memang dapat dikatakan
sebagai budaya yang sangat lumrah. Pada masa itu, belum menjadi familier
menciptakan perkakas dari plastik seperti hari ini sehingga tanah adalah sarana paling
populer untuk menciptakan perabotan. Perabotan-perabotan tanah dari yang paling
sederhana untuk konsumsi pribadi masyarakat hingga industri perabotan yang mewah
diproduksi di sana untuk kebutuhan kelompok elite dan sebagai komoditas ekspor416.
Menjadikan tanah sebagai perabotan adalah sebuah tradisi yang tidak hanya
terjadi dalam masyarakat elite, tetapi juga tradisi tersebut dilakukan oleh masyarakat
umum. Tradisi tersebut terjadi pada masa lalu di hampir seluruh wilayah di Indonesia.
Bahkan, dalam masyarakat umum, dibandingkan pada tingkatan elite, menjadikan
tanah sebagai analogi wujûd yang satu menjelma dalam berbagai bentuk, menjadi
lebih terang. Hal ini karena perabotan yang dibuat dari tanah oleh masyarakat umum
lebih sederhana. Hanya membentuk tanah liat menjadi aneka rupa, seperti gelas,
piring, dan sebagainya secara sederhana. Perabotan masyarakat umum tidak
dicampurkan dengan bahan-bahan lain dan tidak diberi berbagai warna, tetapi
dikeraskan saja. Oleh sebab itu, setelah tanah menjadi berbagai jenis perkakas, seperti
kendi, buyung, periuk, tempat, dan bejana maka semua perabotan tersebut masih
dapat dilihat seperti tanah secara keseluruhannya. Dengan demikian, analogi tanah
menjadi sangat efektif untuk menggambarkan bagaimana wujûd yang dipahami
Hamzah Fansûrî417.
Tanah adalah analogi untuk wujûd, sementara segala perkakas, seperti kendi,
buyung, periuk, tempat, dan bejana adalah analogi untuk makhluk-makhluk. Menjadi
berbagai jenis makhluk itu seperti berbagai bentuk perabotan, seperti kendi, buyung,
periuk, tempat, dan bejana, semuanya berasal dari tanah. Meskipun terdiri atas
415 Jabir,Muhammad Nur Wahdah Al-Wujûd Ibn ‘Arabî dan Filsafat Wujûd Mulla
Sadrâ…., 54. 416 Guillot mengatakan bahwa produk keramik dan perabotan tanah dari Sumatra
memiliki kualitas yang sangat baik. Guillot, Barus: Seribu Tahun Yang Lalu…, 203. 417 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 268 Menurut KBBI daring: Kata ‘kendi’ berarti
tempat air bercerat. Kata ‘buyung’ berarti tempat untuk membawa air yang besar perutnya.
Kata ‘periuk berarti alat untuk menanak nasi. Kata ‘tempat’ dalam konteks perabotan dari
tanah adalah sesuatu yang dipakai untuk menaruh suatu benda, bukan bermakna lokasi. Kata
‘bejana’ berarti benda berongga yang dapat diisi dengan cairan atau serbuk dan digunakan
sebagai wadah.
104
berbagai bentuk, dengan jelas semua perabotan itu dapat diketahui adalah tanah.
Begitu mudahnya masyarakat dapat mengetahui dan memahami ajaran Hamzah
Fansûrî yang dianggap sangat tinggi dan elitis sasaran pengajarannya. Sehingga dapat
dikatakan, ajaran Hamzah Fansûrî itu tidak benar hanya untuk masyarakat yang telah
mencapai tingkatan keilmuan tertentu untuk memahaminya karena memang
perabotan tanah itu dapat dibuat oleh siapa saja dan kapan saja. Dalam hal ini,
bagaimana ternyata ajaran Hamzah Fansûrî sangat dekat dengan keseharian
masyarakat akibat akurasi pemilihan analogi. Sebuah karya memang tidak perlu
diasumsikan sebagai sebuah misteri yang sangat sulit dipahami418.
Pada masa Hamzah Fansûrî, membuat perabotan dari tanah dapat dilakukan
dengan jumlah yang sangat sedikit oleh tiap-tiap anggota keluarga untuk kebutuhan
rumah tangganya saja. Membuatnya juga sangat mudah, yaitu dengan mengambil
tanah di lokasi yang sangat mudah ditemukan, lalu mencetaknya secara mandiri.
Proses pengeringannya juga tidak lama. Hari ini memang masih terdapat produksi
perabotan dari tanah. Akan tetapi, tidak lagi diproduksi secara mandiri. Produksinya
oleh sekelompok orang, lalu dihantarkan ke pasar tradisional untuk didistribusikan419.
Hari ini, perabotan tanah untuk masyarakat umum menjadi kurang diminati
karena sifatnya yang gampang pecah. Pada masa lalu, sifat mudah pecah perabotan
tanah tidak dipermasalahkan karena begitu mudah dan sederhana pembuatannya.
Namun karena perubahan zaman, perabotan tanah mulai ditinggalkan sehingga
perabotan tanah menjadi asing bagi masyarakat. Dengan demikian, analogi tanah
sebagai wujûd juga menjadi kurang dapat dipahami masyarakat. Namun, untuk
membayangkan tanah dengan perabotan dari tanah itu tidak terlalu sulit. Hal yang
perlu diwaspadai adalah membayangkan perabotan-perabotan tanah itu seperti
barang antik peninggalan masa lalu yang harganya sangat mahal420.
Memang benar selain perabotan sederhana oleh dan untuk masyarakat umum,
juga terdapat produksi perabotan mewah, seperti guci, piala, piring, cangkir, dan
sebagainya untuk kelompok elite421. Akan tetapi, benda-benda mewah itu diberikan
tambahan-tambahan tertentu sehingga permukaannya menjadi tidak lagi mirip
dengan tanah. Tentunya memang benar perabotan-perabotan mewah itu juga dibuat
dari tanah. Akan tetapi, kurang sesuai untuk menggambarkan analogi tanah dan
perabotan yang digambarkan Hamzah Fansûrî sebagai analogi ajarannya. Oleh sebab
itu, cara yang baik untuk menggambarkan analogi tanah sebagai Wujûd Haqq Ta’ala
dan perabotan, seperti kendi, buyung, periuk, tempat, dan bejana sebagai wujûd
makhlûqat, adalah sebagaimana perabotan tanah sederhana yang mudah dibuat semua
masyarakat422.
418 Sumaryono, Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat…, 106. 419 Keahlian membuat perkakas rumah tangga secara mandiri di Indonesia telah terjadi
ribuan tahun lalu. Lihat, Juniar Hutahean and Cici Ramadayani Sirait, “Analisis Nilai
Resistivitas Di Tanah Peninggalan Sejarah Purbakala Menggunakan Metode Geolistrik Di
Daerah Lobu Tua Kabupaten Tapanuli Tengah,” Einstein e-Journal 5, no. 3 (January 9, 2019),
27 https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/einsten/article/view/12003. 420 Gullot, Barus: Seribu Tahun Yang Lalu…, 219. 421 Melissa de la Cruz, Blue Bloods, (Jakarta: GagasMedia, 2011), 59. 422 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 268.
105
Tuhan itu yang Esa itu Wujud-Nya dianalogikan dengan tanah. Sementara
wujud alam semesta atau makhluk-makhluk itu seperti eksistensi, seperti kendi,
buyung, periuk, tempat, dan bejana. Sebenarnya semua benda itu adalah tanah, tetapi
penampakan-penampakannya, seperti kendi, buyung, periuk, tempat, dan bejana.
Lebih sederhananya lagi, dalam konteks relasi tanah dan berbagai perabotan ini,
Hamzah Fansûrî hanya ingin mengatakan bahwa makhluk-makhluk memperoleh
eksistensi dari Tuhan. Alam semesta mengada dengan wujûd yang diberikan oleh
Tuhan423.
“Seperti tanah; diperbuat kendi, atau periuk, atau buyung, atau tempat. Tanah
itulah asal wujûd sekalian bejana itu. Jika tiada tanah itu, di mana kendi dan
periuk akan beroleh wujûd?”424
7. Mahatari dan Sinarnya sebagai Pemberian Wujûd
Mengenai analogi cahaya dan sinarnya, Hamzah Fansûrî menulis:
Chahaya Athtar-Nya tiadakan padam
Memberikan wujûd sekalian alam
Menjadikan makhluq siang dan malam
Ila [abadi] i’bad tiada ‘kan karam.425
Hamzah Fansûrî menggunakan matahari sebagai analogi Wujûd Haqq Ta’âlâ.
Matahari dan sinar matahari meskipun sebenarnya satu, hakikatnya adalah satu.
Demikianlah Hamzah Fansûrî menggambarkan analogi perbedaan wujûd antara
Bâsîth dan makhlûqat sebagaimana dipegang oleh para mutakallimîn. Sementara
Hamzah Fansûrî sendiri menggunakan analogi cahaya (cahaya matahari dan
sinarnya) meskipun terkesan berbeda, sejatinya adalah satu cahaya, yakni cahaya
matahari426. Adapun Wujûd Al-Haqq dianalogikan sebagai “matahari” dan wujûd
selain Al-Haqq dianalogikan dengan “sinarnya”. Analogi ini untuk menjelaskan
bahwa wujûd selain Al-Haqq dalam pandangan ‘urafâ adalah bayangan Al-Haqq.
Dalam sejarah panjang tradisi intelektualisme, cahaya telah menjadi simbol
bagi hal-hal positif yang dikontraskan dengan kegelapan sebagai simbol-simbol
negatif. Cahaya memang sangat mudah dipahami. Begitu terangnya hingga tidak ada
apa pun yang lebih terang darinya sehingga tidak ada konsep apa pun yang dapat
digunakan untuk mendefinisikan cahaya427. Sama seperti para pemikir sebelumnya,
Hamzah Fansûrî juga tidak dapat menghindar dari menggunakan konsep cahaya
untuk membantu menjelaskan ajarannya. Cahaya yang mudah saja dikaitkan dengan
Haqq Ta’âlâ membuat menjadi suatu sesuatu yang sangat terang hingga menyinari
apa pun, termasuk alam materi. Dalam analogi cahaya, terkait dengan konteks
423 Hamzah Fansûrî, “Syarâb Al-Asyiqîn,” dalam The Mysticism of Hamzah Fansuri,
Syed Muhammad Naquib Al-Attas (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1970), 302 424 Hamzah Fansûrî, “Syarâb Al-Asyiqîn,” …, 268. 425 I Hamzah Fansûrî, “Syarâb Al-Asyiqîn,” …, 236. 426 Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri…, 128. 427 Miswari, Filsafat Terakhir…, 484.
106
menjelaskan hubungan Haqq Ta’âlâ dengan alam maka alam menjadi pancaran dari
cahaya428.
Syed Muhammad Naquib Al-Attas, menjelaskan, dalam skema Hamzah
Fansûrî, “Chahaya Athtar-Nya tiadakan padam/ Memberikan wujûd sekalian alam/
Menjadikan makhluq siang dan malam/ Ila [abadi] i’bad tiada ‘kan karam429”,
maksudnya adalah Hamzah Fansûrî lebih dahulu menganalogikan wujûd dengan
tanah, lalu wujûd dibagi menjadi wujûd hakiki yang terbagi menjadi wujûd jam’i,
wujûd tamyizî, wujûd mufassalî, dan wujûd wahmî sebagai wujûd kharijî; yakni
aktualitas alam semesta yang terindrai dan terjangkau inteleksi. Maka dari itu, wujûd
alam memperoleh eksistensi secara terus-menerus (siang dan malam) sebagai sebab
(athar) dari Haqq Ta’âlâ. Aktivitas pemberian wujûd itu seperti kejadian perabotan
yang memperoleh wujûd dari tanah430.
Hamzah Fansûrî mengatakan bahwa dalam pandangan ‘urafâ, Wujûd Allah
dan wujûd alam itu esa. Bila berbeda, dapat dikatakan Allah dan alam itu adalah dua
entitas yang tunggal. Hamzah Fansûrî menulis:
“Wujûd Allah dengan wujûd alam esa. Esa, wujûd ‘alam dengan ‘alam esa
hukumnya. Seperti (matahari dengan) chahayanya, namanya jua lain pada
haqiqat tiada lain. Pada penglihatan mata esa; pada penglihatan hati pun esa.
Wujûd ‘alam pun demikian dengan Wujûd Allah: esa. Karena alam tiada ber-
wujûd sendirinya. Sungguh pun pada zahirnya ada ia ber-wujûd, tetapi wahmî
juga, bukan haqiqî.” 431
Cahaya adalah analogi yang paling sering digunakan kaum ‘urafâ. Analogi ini
tidak hanya dipakai oleh kaum ‘urafâ, tetapi juga sebagian filosof tertentu. Bahkan,
analogi cahaya telah dipakai oleh filosof Persia kuno Zarathustra432. Begitu akuratnya
analogi ini, bahkan Allah menggunakan analogi ini dalam Al-Qur’an surah An-Nuur
ayat ke-35433.
نور السموت والرض مثل نوره كمشكوة فيها مصباح جاجة كانها كوكب للاه المصباح في زجاجة الز
ء و يكاد زيتها يضي ل غربية بركة زيتونة ل شرقية و ي يوقد من شجرة م لو لم تمسسه نار نور در
ل بكل شيء عليم على نور يهدى للاه المثال للناس وللاه نوره من يشاء ويضرب للاه
Artinya:
“Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya, seperti sebuah
lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di
dalam tabung kaca (dan) tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan,
428 Menurut Abdul Hadi W.M., Alquran menjadi cahaya bagi Hamzah Fansûrî untuk
menginspirasi pemikiran-pemikirannya. Lihat, Hadi WM. Abdul, Tasawuf Yang Tertindas…,
9–220. 429 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn”…, 236. 430 Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri…, 143. 431 Al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansûrî…, 242. 432 Iqbal, Allama Sir Muhammad Metafisika Persia… 37. 433 Ula, “Simbolisme Bahasa Sufi: Kajian Hermeneutika Terhadap Puisi Hamzah
Fansûrî.”
107
yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, (yaitu) pohon
zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya
(saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas
cahaya (berlapis-lapis), Allah memberi petunjuk kepada cahaya-Nya bagi
orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan
bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”
Pada ayat di atas disebutkan Allah sebagai cahaya. Salah satu sifat Allah adalah
al-Nûr. Tentu saja cahaya yang dimaksud bukanlah Zat-Nya, tetapi kemiripan sifat
cahaya dengan sifat Tuhan yang dapat dibayangkan pikiran manusia434. Cahaya
adalah analogi sederhana yang dapat dipahami oleh siapa pun dari berbagai bangsa,
berasal dari mana pun, dan pada waktu kapan pun. Sebab itulah dalam hampir semua
literatur pada setiap generasi, khususnya terkait dengan ilmu pengetahuan dan
spiritualisme, cahaya selalu mendapatkan tempat penting sebagai sebuah simbol. Dari
literatur-literatur pengetahuan Babilonia, Persia, Mesir, Yunani, Islam, hingga Barat
Modern, cahaya selalu mendapatkan tempat penting. Di Persia, Zarathustra
menjadikan cahaya sebagai analogi penting dan api sebagai acuan konsepnya.
Sementara di Yunani, Plotinus mengembangkan konsep emanasi dari semangat sifat
cahaya. Dalam Islam, kitab suci Al-Qur’an, tasawuf Abû Hamid al-Ghazalî, dan
filsafat Syihab al-Dîn al-Suhrawardî memiliki peran penting untuk menjadi simbol
suatu ajaran. Sebagaimana disebutkan William Chittick, biasanya simbolisme cahaya
sebagai analogi untuk konotasi positif, seperti kebaikan dan dikontraskan dengan
kegelapan sebagai konotasi negatif, seperti kegelapan435.
Pandangan Hamzah Fansûrî yang menganalogikan Tuhan seperti matahari dan
makhluk-makhluk dianalogikan cahayanya. Dalam hal ini menunjukkan bahwa alam
semesta bukan merupakan suatu ketiadaan, tetapi merupakan sesuatu yang nyata,
tetapi tidak memiliki wujûd mandiri. Wujûd Alam adalah diberikan oleh Wujûd
Tuhan, sama seperti matahari yang esa dengan cahayanya436. Cahaya merupakan
analogi sederhana yang sangat mudah diterima umat Islam. Analogi tersebut dibuat
sendiri oleh Tuhan untuk menggambarkan sifat-Nya. Analogi tersebut tercantum
dalam Al-Qur’an Surah An-Nur: 35 yang menyatakan bahwa Allah adalah cahaya
langit dan bumi. Pernyataan tersebut tentu bukan sebuah gambaran kondisi Dzat
Tuhan, melainkan sifatnya tentang bagaimana Tuhan menjadi penerang kehidupan
manusia437.
Menganalogikan Tuhan sebagai cahaya telah dilakukan sejak agama-agama
sebelum Islam. Bahkan, analogi tersebut telah digambarkan dalam agama Zoroaster
yang merupakan salah satu agama tertua. Agama-agama lainnya juga tidak pernah
meninggalkan analogi cahaya yang umumnya berorientasi pada kebaikan dan
434 Nasr, Seyyed Hossein, “Existence (Wujūd) and Quiddity (Māhiyyah) in Islamic
Philosophy,” International Philosophical Quarterly 29, no. 4 (1989): 409. 435 William C. Chittick,, Ibn ’Arabi: Heir to the Prophet, (Oxford: Oneworld, 2005),
118. 436 Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri…, 128. 437 Rasmianto, “Mengurai Problem Dikotomik Eksistensial Manusia Dalam Perspektif
Agama Dan Teori Evolusi,” El-Harakah 6, no. 2 (August 13, 2008): 75..
108
dikontraskan dengan kegelapan sebagai analogi untuk keburukan438. Ketika Hamzah
Fansûrî menggambarkan bagaimana kondisi Tuhan melalui analogi cahaya, tentu
analogi tersebut dapat dengan sangat mudah dipahami seluruh lapisan masyarakat.
Hal ini kembali menunjukkan bagaimana Hamzah Fansûrî selalu menggunakan
analogi-analogi sederhana dalam menggambarkan manusia sehingga sangat mudah
dipahami. Maksud Hamzah Fansûrî menggunakan analogi kesatuan matahari dan
cahayanya adalah untuk menjelaskan bahwa meskipun Wujûd Tuhan dan wujûd
makhluk pada pandangan manusia itu berbeda, hakikatnya adalah satu wujûd, yakni
Wujûd Tuhan. Makhluk-makhluk memperoleh wujûd dari Wujûd Tuhan sehingga
meskipun tidak memiliki wujûd sejati, makhluk-makhluk tetap memiliki wujûd yang
mana wujûd tersebut dari Wujûd Tuhan439.
8. Kayu dan Buah Catur sebagai Hubungan Ketunggalan dan
Kemajemukan
Selain tanah dan segala perabotan, Hamzah Fansûrî juga menggunakan catur
dan buah catur untuk menganalogikan hubungan Tuhan dan makhluk. Di samping
itu, catur dalam analogi Hamzah Fansûrî juga digunakan untuk menganalogikan
kekuasaan Tuhan dibandingkan keinginan makhluk. Selanjutnya, analogi catur juga
untuk menjelaskan bagaimana makhluk-makhluk memiliki nama-nama, tetapi tidak
memiliki hakikat440.
Mengenai analogi kayu dan buah catur, Hamzah Fansûrî menulis:
“Adapun suatu tamthil lagi mithal [buah] chatur. Asalnya kayu sepuhun jua.
Maka dilarik berbaga-bagai; dinamainya raja, dan menteri, dan gajah, dan
kuda, dan tir dan baidaq. Asalnya kayu sekerat juga dijadikan banyak”441
Menariknya, dalam analogi kayu terdapat tiga perspektif analogi. Analogi
pertama adalah bagaimana berbagai bentuk buah catur yang berbeda-beda adalah
sebenarnya berasal dari satu entitas saja, yakni dari kayu. Menjadi beragam seperti
Wujûd Bâsîth yang tunggal, tetapi muncul berbagai keberagaman bentuk maklûqat
sebagaimana keberagaman bentuk buah catur yang sebenarnya kayu. Perspektif
analogi kedua adalah berada dalam konteks kefakiran makhlûqat. Makhlûqat itu
seperti biji catur. Sama sekali tidak memiliki daya untuk mengendalikan dirinya.
Semuanya sangat bergantung pada Bâsîth sebagaimana sangat bergantungnya biji
catur kepada pemain catur. Analogi ketiga adalah, sebagaimana nama-nama biji
catur; raja, menteri, gajah, kuda, benteng, dan bidak, namun hakikatnya hanya
artifisial saja. Tidak ada raja, menteri, gajah, kuda, benteng, dan bidak di sana.
Semuanya hanya dilekatkan nama-nama saja. Demikian juga makhlûqat itu
semuanya hanya merupakan nama-nama artifisial, tidak memiliki wujûd nyata, hanya
438 Chittick, Ibn ’Arabi: Heir to the Prophet…, 118. 439 Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri…, 128. 440 Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri…, 294. 441 Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri…, 294.
109
bayangan. Hal ini karena sejatinya hanya merupakan kesatuan Tunggal Haqq Ta’âlâ 442.
Catur adalah salah satu jenis permainan yang telah berumur sangat tua, populer
untuk setiap zaman, dan masih sangat diminati hingga hari ini. Permainan catur telah
dikenal sejak zaman abad keenam Masehi. Permainan tersebut diperkenalkan di
India, menjalar ke Persia, dan kawasan-kawasan lain di dunia. Sistem permainan
catur diinspirasikan dari formasi pasukan dalam epos “Mahabaratha”. Permainan ini
awalnya dimainkan elite Gupta dalam mengisi waktu luang, mengasah teknik
berpikir, dan menemukan inspirasi strategi perang443. Dari India, catur dengan cepat
berkembang ke Persia, dimainkan oleh elite Sassanid. Tidak lama kemudian, setelah
Islam menguasai Persia, permainan tersebut menjadi permainan populer dalam dunia
Islam. Melalui tangan Islam, catur dibawa ke Spanyol dan Portugal. Selanjutnya,
menyeberang ke kawasan lain di Eropa444. Sebagai ilmuwan yang telah lama menetap
di Timur Tengah, tentu saja Hamzah Fansûrî sangat mengenal permainan catur. Akan
tetapi, tentu saja catur tidak akan dijadikan analogi dalam menjelaskan ajarannya
apabila permainan tersebut belum dikenal di Aceh pada masa itu445.
Secara umum, dianggap permainan catur baru hadir di Indonesia dibawa oleh
Kolonial Belanda. Namun sebenarnya, permainan tersebut telah ada di Indonesia
sejak kerajaan-kerajaan Islam berdiri di Indonesia. Tentu saja pada masa Kesultanan
Aceh Darussalam, permainan tersebut telah dikenal luas karena Aceh Darussalam
merupakan negeri yang sangat padat dan telah memiliki hubungan yang sangat dekat
dengan Baghdad yang telah mengadopsi permainan catur dari Persia. Bahkan tidak
hanya itu, jauh sebelumnya, Kesultanan Pasai sendiri telah memiliki relasi yang
sangat dekat dengan Baghdad dan negeri-negeri lainnya yang telah memopulerkan
catur. Hal ini ditunjukkan dengan jaringan kesarjanaan dan keilmuan yang sangat
lancar antara Samudra Pasai dan Timur Tengah serta Cina dan Eropa446. Dengan
demikian, tentunya di negeri tempat Hamzah Fansûrî lahir dan menyebarkan
ajarannya, tentu saja catur telah menjadi sangat familier bagi masyarakat di sana.
Bahkan, negeri Melayu yang merupakan negeri tropis, tentu saja masyarakatnya
dengan sangat mudah memanfaatkan kayu untuk berbagai keperluan, termasuk
menciptakan berbagai alat permainan, termasuk catur. Hal inilah yang membuat
Hamzah Fansûrî menggunakan catur sebagai analogi ajarannya447.
Apabila penyebaran catur di Eropa dibawa melalui ekspansi Kekhalifahan
Umayyah, maka tentunya ke Indonesia juga telah diperkenalkan catur pada masa
tersebut. Karena, hubungan Indonesia dan Timur Tengah telah terjadi pada periode
Dinasti Umayyah448. Namun tentunya permainan tersebut pada masa ini belum terlalu
442 Al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansûrî…, 294. 443 Claude Levi-Strauss, Claude- Levi-Strauss (Yogyakarta: LKiS, 2000), 120–121. 444 K. Bertens,, Panorama Filsafat Modern (Jakarta: Teraju, 2005), 10. 445 Hamzah Fansûrî hidup dan berkarier pada sekitar abad ke-15 atau abad ke-16. Lihat,
Al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansûrî…, 7–9; Drewes dan Brakel, The Poems of
Ḥamzah Fansûrî…, 3–5; Abdul Hadi WM., Tasawuf Yang Tertindas…, 137–138. 446 Said, Aceh Sepanjang Abad Vol. I…, 89. 447 Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri…, 172. 448 Philip K. Hitti,, History of the Arab (London: Macmillan, 1990), 423.
110
dikenal masyarakat umum. Adapun pada periode Kesultanan Aceh Darussalam, dapat
diasumsikan permainan catur telah dikenal luas. Karena itulah Hamzah Fansûrî
menggunakan catur sebagai analogi ajarannya. Kurang dapat diterima apabila catur
hanya menjadi permainan bangsawan, tetapi digunakan sebagai analogi ajarannya.
Hal ini bertentangan dengan bagaimana ketika menggunakan perabotan tanah yang
merupakan analogi yang dikenal masyarakat umum. Demikian juga dengan analogi-
analogi lainnya, semua analogi yang digunakan Hamzah Fansûrî adalah analogi-
analogi yang dekat dengan keseharian seluruh masyarakat449.
Meskipun tidak semua masyarakat umum menyukai permainan catur, namun
pada masa itu dapat dikatakan mereka telah mengenal permainan tersebut meskipun
tidak semuanya suka memainkannya. Kalaupun dianggap permainan catur hanya
dimainkan oleh kalangan elite, besar kemungkinan hampir semua lapisan masyarakat
dapat mengenal permainan tersebut. Lagi pula, kecil kemungkinan permainan catur
tidak dimainkan masyarakat umum. Meskipun tidak semua orang menyukai
permainan tersebut karena terlalu membutuhkan kecakapan berpikir, permainan catur
tentu dikenal setiap masyarakat karena masyarakat Indonesia yang umumnya bertani
dan melaut, memiliki waktu yang banyak untuk berkumpul sambil menunggu musim
bersibuk-sibuk di sawah dan ladang serta menunggu angin laut kondusif untuk
mencari ikan. Tentu saja waktu luang yang banyak untuk berkumpul dalam rangka
menghindari jenuh dan bosan, mereka mengisinya dengan permainan-permainan,
seperti catur. Lagi pula, Indonesia yang tropis membuat masyarakat sangat dekat
dengan kayu. Banyak jenis peralatan dibuat dari kayu sehingga tentu saja membuat
permainan catur menjadi sangat mudah bagi mereka450.
Masa Kesultanan Samudra Pasai telah memiliki hubungan yang sangat erat
dengan Timur Tengah sehingga sangat mungkin catur telah diperkenalkan di
Indonesia pada masa tersebut. Bila benar, meskipun awalnya catur adalah konsumsi
elite, dalam waktu yang tidak terlalu lama, tentu permainan tersebut telah dikenal
masyarakat umum. Catur adalah permainan mengasyikkan yang dilakukan dalam
durasi yang tidak singkat. Untuk itu, sudah barang tentu permainan tersebut hanya
dengan mudah dilakukan kalangan elite dan petani dan nelayan yang punya banyak
waktu senggang. Mereka punya waktu yang banyak untuk bersantai dan mengisinya
dengan liburan. Kalangan elite perlu selalu mengasah pikiran karena mengemban
banyak tanggung jawab yang menuntut kecerdasan pikiran. Teknik-teknik catur juga
sangat membantu dalam menjaga karier politik. Sementara untuk masyarakat biasa,
hanya untuk mengisi waktu luang451.
Sementara masyarakat umum harus meluangkan banyak waktu untuk bekerja
keras demi mempertahankan hidup sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk
449 Amsal Bakhtiar, Tasawuf dan Gerakan Tarekat (Bandung: Angkasa, 2003), 59;
Oman Fathurahman,, Tanbih Al-Masyi: Menyoal Wahdah al-Wujûd : Kasus Abdurrauf
Singkel Di Aceh Abad 17 (Bandung: Mizan, 1999), 53. 450 Hamzuri dan Siregar menjelaskan bahwa permainan catur telah lama menjadi tradisi
di Aceh. Biasanya permainan tersebut dimainkan di meunasan atau di bawah rumah Aceh.
Lihat, Hamzuri dan Tiarma Rita Siregar, Permainan Tradisional Indonesia (Jakarta:
DIrektorat Permuseuman, 1998), 25–26. 451 Nurilla Iryan, 365 Ideas of Happiness, (Yogyakarta: Bentang Belia, 2019), 56.
111
bermain catur. Akan tetapi, kondisi masyarakat agraris di Aceh yang hanya sibuk
bekerja pada musim panen dan musim tanam, membuat mereka punya banyak waktu
luang. Kesempatan itu tentunya dapat diisi dengan bermain catur452. Lagi pula,
membuat alat permainan catur itu tidak terlalu sulit. Hanya membutuhkan kayu yang
diratakan sebagai papan catur, kotak dua pemain diberi tanda tertentu dengan ukiran
tertentu untuk membedakan. Lalu, dari kayu juga dibuat berbagai bentuk sesuai
dengan fungsi tiap buah catur, seperti raja, menteri, gajah, kuda, benteng, dan bidak.
Untuk membedakan dua pihak pemain, tiap-tiap biji catur dapat diukir dalam bentuk
berbeda atau diberi ukiran tertentu. Bisa pula diberi warna berbeda453.
Dengan mempertimbangkan kondisi sosiokultural masyarakat dan mudahnya
menemukan bahan untuk membuat buah catur maka dapat dikatakan begitu mudah
catur dapat diakses masyarakat umum. Bila benar, tentunya analogi kayu sebagai
Wujûd Haqq Ta’ala menjadi berbagai bentuk buah catur sebagai analogi beragam
bentuk dalam realitas, digunakan Hamzah Fansûrî karena memang permainan
tersebut sangat dekat dengan semua masyarakat.
Kemungkinan penggunaan analogi catur sebagai ajarannya adalah karena
permainan tersebut sangat dekat dengan masyarakat didukung oleh kenyataan
analogi-analogi lain yang digunakan selalu adalah objek-objek yang dekat dengan
masyarakat. Apalagi masyarakat Melayu, selain melalui analogi yang dibuat Hamzah
Fansûrî, telah lumrah diketahui bahwa catur memang merupakan bagian dari
permainan tradisional di sana. Bahkan sebagaimana dikemukakan oleh Hamzuri dan
Siregar, terdapat beberapa jenis permainan catur yang menjadi bagian dari permainan
tradisional di Aceh.454.
Menggunakan kayu sebagai analogi hubungan Wujûd Tuhan dengan beragam
maujud (ekstensi, mawjûdat) alam semesta sangat mudah dipahami. Karena
meskipun terdapat berbagai bentuk kayu dalam biji-biji catur, hakikatnya
keseluruhan biji catur adalah kayu. Menjadi berbagai bentuk dan diberikan berbagai
nama hanyalah penyebutan. Sejatinya, semua itu adalah dari satu, yakni kayu.
Demikianlah dalam pandangan sufi, meskipun terdapat beragam mawjûdat dalam
realitas, sejatinya semua itu tidak nyata karena yang nyata hanya Wujûd Haqq Ta’ala.
Analogi kayu sebagai biji-biji catur juga menggambarkan bahwa segenap makhluk
itu sama sekali tidak memiliki daya. Setiap makhluk secara total dikendalikan oleh
Tuhan. Persis seperti buah catur. Semuanya tidak dapat sama sekali bergerak dengan
keinginannya, kecuali digerakkan oleh pemain catur.
Melalui analogi buah catur, dapat ditunjukkan pula bagaimana alam semesta
ini sebenarnya hanyalah sebagai penamaan-penamaan. Seperti di atas papan catur
tidak ada raja, tidak ada menteri, tidak ada gajah, tidak ada kuda, tidak ada benteng,
452 Meskipun meripakan permainan dan hiburan para elit untuk mengisi waktu luang.
tetapi tetap dimanfaatkan masyarakat uumum juga untuk mengisi waktu luang. Lihat Hitti,
History of the Arab…, 423; Hamzuri dan Siregar, Permainan Tradisional Indonesia…, 25–
26. 453 Adapun nama-nama familiar untuk buah catur adalah: raja, menteri, gajah, kuda,
benteng, dan bidak. Sementara Hamzah Fansûrî menyebutnya: raja, dan menteri, dan gajah,
dan kuda, dan tir dan baidaq.Lihat, Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 294. 454 Hamzuri dan Siregar, Permainan Tradisional Indonesia…, 25–26.
112
dan tidak ada bidak. Hanya kayu yang dibentuk dengan berbagai rupa yang ada.
Demikian pula alam semesta sejatinya hanya penamaan semata karena yang nyata
hanya satu, yakni Tuhan.
9. Laut dan Ombak sebagai Makhluk Menjadi Jejak Ilahi
Mengenai analogi laut dan ombak, Hamzah Fansûrî menulis:
Tuhan kita itu seperti Bahr al-‘Amiq
Ombaknya penuh pada sekalian tariq
Laut dan ombak keduanya rafiq
‘Akhirnya kedalamnya jua ombaknya qhariq.
Pembagian analogi laut terbagi dua, yakni Bahr al-‘Amiq sebagai Dzat Bâsîth
yang tiada terperi atau tidak teridentifikasi oleh siapa pun, termasuk para nabi dan
malaikat muqarrabin. Nabi Muhammad berkata, “Maha Suci Engkau, tiada kukenal
Diri-Mu dengan sempurna kenal”455. Sementara analogi laut yang berelasi dengan
ombak adalah untuk menganalogikan Bâsîth dalam hubungannya dengan makhlûqat.
Inspirasi ‘urafâ dalam menggunakan analogi bisa dikatakan dari berbagai
sumber. Bahkan, ada dari Al-Qur’an seperti analogi laut sebagaimana tertera dalam
Al-Qur’an Surat 48:10; 8:17; dan 50:16. Namun, yang paling diutamakan adalah
kesesuaian esensi sesuatu yang mereka jadikan objek analogi dengan manifestasi
nama-nama Ilahi yang mereka terima dalam pengalaman hudhûrî456.
Lautnya “Alim halunya Ma’lûm
Keadaannya Qasim ombaknya Maqsum
Tufannya Hakim shu’unnya Mahkum
Pada sekalian ‘alamin inilah rusum457.
Adapun laut dianalogikan sebagai Haqq Ta’âlâ . Ombak dianalogikan sebagai
segala realitas selain Haqq Ta’âlâ. Laut yang dimaksud ‘urafâ adalah alam hakikat
yang tidak terbatas. Insan pada sisi lain, sebagai mikrokosmos, adalah setetes air.
Oleh karena itu, dirinya yang setetes itu harus ditenggelamkan ke dalam lautan Ilahi.
Ini adalah jalan yang diperintahkan Nabi saw. dalam pesan yang tersirat458.
“Ya’ni laut dan ombak keduanya bertaulan; mithal hamba dengan
Tuhan,’asyiq dan ma’shuq’459.
Laut dianalogikan sebagai syu’un Allah dan dan Pengetahuan-Nya sebagai
“ombak”. Tujuan penggunaan analogi tersebut dalam konteks ini adalah untuk
455 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 271. 456 Fathul Mufid, “Epistemologi Ilmu Hudhuri Mulla Shadra,” Al-Qalam 29, no. 2
(August 31, 2012): 215. 457 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 236. 458 Kautsar Azhari Noer,, Ibn ‘Arabi: Wahdat Al-Wujûd Dalam Perdebatan, 128. 459 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 272.
113
menyatakan bahwa sebenarnya yang nyata hanyalah Dia. Karena itu, yang Dia
ketahui tentunya adalah syu’un-nya itu. Hal ini karena laut dengan ombak adalah satu
sebab ombak sebenarnya adalah laut juga. Jika diamati, analogi ini menjadi sangat
akurat. Laut yang dalam (bahr amîq) adalah analogi untuk menggambarkan Dzat
Allah yang tiada dapat diidentifikasi. Kedalaman laut yang tiada terperikan mungkin
kini sebagian sudah dapat ditembus dan dieksploitasi melalui teknologi-teknologi
sehingga setiap detail dari kedalaman laut dapat dianalisis, tetapi laut sebagai yang
tiada berhingga dan tiada berkesudahan460 tidak mampu dianalisis sepenuhnya. Di
samping itu, masih sangat banyak rahasia-rahasia kedalaman laut yang belum mampu
diidentifikasi. Bahkan hal-hal yang telah dapat dianalisa sebagai kandungan di
kedalaman laut masih lebih sedikit daripada yang belum tereksplorasi. Bahkan hal-
hal yang telah dan akan dapat dieksplorasi dari laut adalah hal-hal yang memiliki
keterhinggaan dan batas-batas461.
Jika ada akan dia hingga dan kesudahan, atau awal dan akhir berarti adalah
makhluk juga, bukan Bahr al-’Amiq. Karena itu, Ibn ‘Arabî menegaskan bahwa Al-
Haqq mustahil dapat didefinisikan. Karena definisi adalah pembatasan, ketika yang
tak terbatas dibatasi maka jadinya bukan lagi yang tidak terbatas.
“Hamzah Fansûrî terlalu karam
Didalam laut yang mahadalam
Berhenti angin ombakpun padam
Menjadi Sultan daripada kedua ‘alam”
Hubungan antara laut dan ombak seperti seseorang dengan sifat-sifatnya:
“Seperti seorang Muhammad namanya; jika ia ber’ilmu, ‘alim namanya; jika
ia pandai, utus namanya; jika ia tahu menyurat, katib namanya; jika ia
berniaga; saudagar namanya.”462
Misalnya, seseorang bernama Muhammad. Akan tetapi, diberi banyak nama
lainnya tergantung sifat-sifatnya. Ketika dia berilmu, diberi nama ‘alim’. Ketika dia
punya keahlian tertentu disebut utus. Ketika dia menulis, disebut katib. Ketika dia
berdagang, disebut saudagar. Demikian juga nama-nama Allah karena menjadikan
makhluk disebut Khaliq. Ketika memberikan rezeki disebut Raziq. Nama-nama itu
semua berada di bawah nama Allah. Ketika disadari bahwa Dzat-Nya tidak dapat
diketahui siapa pun, disebut Huwa463.
Analogi laut dan ombak itu dianalogikan dalam menjelaskan tentang Sifat ‘Ilm
Haqq Ta’âlâ. Dia ‘Ilm maka memiliki Ma’lûm. Hubungan ‘Alim dan Ma’lûm disebut
‘Ilmû. ‘Ilmu menghasilkan Ma’lûm. ‘Ilmu itu sifatnya tetap. Sementara Ma’lûm itu
tidak. Sebagaimana analogi ‘Ilmû itu adalah laut. Sifatnya tetap. Sementara ma’lûm
460 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 272., 271. 461 Stocker, Roman “Marine Microbes See a Sea of Gradients,” Science, 2012, 628-
633. 462 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 240. 463 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 242.
114
itu dianalogikan dengan ombak. Ombak sifatnya tidak tetap. Ombak muncul dari laut
yang tetap.
Untuk melengkapi pandangan tersebut, yakni tentang ketetapan ‘Ilmû Bâsîth,
Hamzah Fansûrî mengutip pandangan Ibn ‘Arabî yang menyatakan bahwa dahulunya
‘Ilmû Bâsîth itu seperti huruf mahatinggi tak terjamah, tergantung dengan istananya
di puncak gunung.
“Mithal laut; jika tiada laut, ombakpun tiada akan timbul; demikian rupa
ma’lûmat timbul daripada ilmu.”464
Hamzah Fansûrî mengatakan, “Hai Thalib, alam ini seperti ombak”. Hamzah
Fansûrî bermaksud menegaskan bahwa mustahil alam semesta ini muncul dari
ketiadaan karena selain bertentangan dengan kaidah akal, juga bertentangan dengan
Al-Qur’an (36:82) karena di sana sebelum alam semesta menjelma, ketika hendak
menjelmakan alam, Allah berkata kûn, yaitu jadilah465. Bila alam itu tiada sebelum
menjelma, mustahil Allah berucap pada ketiadaan. Lagi pula, bila alam semesta
berasal dari ketiadaan, lalu kembali menjadi tiada maka terjadi perubahan pada Allah,
yaitu dia menjadi sha’an (sibuk)466 ketika ada alam, tetapi menjadi tidak sibuk ketika
alam belum ada atau telah menjadi tiada nantinya.
Allah Ta’ala seperti laut. Sungguhpun ombak lain daripada laut, kepada
haqiqatnya tiada lain daripada laut…”467
Hal-hal yang terjangkau, baik itu hudhûrî maupun hushûlî, atau burhanî,
bayanî, nazarî, dan ‘irfanî itulah yang dapat menjadi pembahasan filsafat dan
tasawuf. Laut dan ombak adalah analogi sederhana untuk menggambarkan
bagaimana kemajemukan muncul dari ketunggalan.
“Ya’ni laut dan ombak keduanya bertaulan; mithal hamba dengan Tuhan,
‘asyiq dan ma’syuq,”468.
Analogi Tuhan sebagai laut dan ombak sebagai makhluk meniscayakan Tuhan
dan makhluk itu bukan dualitas. Namun di alam, Tuhan itu bukan di atas, bukan di
bawah, bukan di kiri, bukan di kanan, bukan di depan, dan bukan di belakang.
Bagaimana bahwa makhluk bukan dari ketiadaan dan bukan kembali menjadi tiada
sebagaimana pandangan mutakallimîn, melainkan dari keberadaan dan kembali
kepada keberadaan. Seperti ombak, muncul dari laut dan kembali ke laut. Allah
disebut sebagai asyîq dan makhluk disebut sebagai ma’syûq. Sebagai analogi laut,
464 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 259. 465 QS. Yasin: 36: Quraish Shihab, (Penerj.) Al-Qur'an dan Maknanya, II. (Jakarta:
Lentera Hati, 2013), 445. 466 QS. Ar-Rahman: 29 Quraish Shihab, (Penerj.) Al-Qur'an dan Maknanya, II.
(Jakarta: Lentera Hati, 2013), 532. 467 Kutipan dari Fansûrî, “Syarâb Al-Asyiqîn,”…, 319. 468 Fansûrî, “Syarâb Al-Asyiqîn,”…, 272.
115
Dia adalah qasîm, yakni yang dibagi, sementara ombak sebagai makhluk disebut
maqsûm. Yang dibagi adalah padanya, bagian-bagian juga padanya. Namun,
sejatinya maqsûm adalah dari qasîm seperti alam yang memperoleh wujûd (maqsûm)
dari Allah (maqsûm)469. Pembagian ini adalah pada sistem inteleksi yang muncul dari
kecenderungan nama dan sifat. Dengan beragam Nama dan Sifat Allah maka
menjadi, melalui kûn yang dianalogikan dengan berbagai macam kejadian, berbagai
macam keadaan, berbagai macam predikasi yang dapat tufan diberikan, dan
seterusnya yang mana semua itu umpama ombak-ombak adalah karena
kecenderungan-kecenderungan Nama-nama dan Sifat-sifat470. Segala kejadian itu
adalah syu’ûn Allah, yakni aktivitas-Nya yang terjadi terus-menerus.
Masyarakat Melayu adalah masyarakat yang mendominasi pesisir. Orang
Melayu umumnya tidak benar-benar jauh dari laut. Oleh sebab itu, selain bertani,
mata pencaharian masyarakat juga sebagai nelayan sehingga laut adalah sesuatu yang
sangat dekat dengan dunia masyarakat Melayu. Bahkan, terdapat kelompok tertentu
yang hanya tinggal di laut471
Dengan menjadikan laut sebagai objek analogi ajarannya maka Hamzah
Fansûrî telah memilih analogi yang sangat dekat dengan masyarakat Kepulauan
Indonesia. Sementara itu, Hamzah Fansûrî sendiri adalah seorang sufi yang sangat
akrab dengan lautan. Dia adalah sosok yang sangat suka mengunjungi tempat-tempat
yang jauh, seperti Timur Tengah472. Perjalanan-perjalanan itu tentunya ditempuh
melalui lautan. Di juga berkarier di kota pelabuhan. Karena itu, Hamzah Fansûrî dan
lautan itu hampir tidak dapat dipisahkan. Menggunakan laut sebagai analogi
ajarannya tentu benar-benar dapat diresapi dengan baik oleh Hamzah Fansûrî.
Dengan demikian, menggunakan analogi tersebut tentu merupakan sebuah hasil
pengamatan refleksi yang mendalam sehingga berhasil menemukan kesamaan sifat
antara laut sebagai objek analogi dan maksud acuan yang dianalogikan.
Setelah mengakui bahwa yang akan dikemukakan hanya sebuah kiasan, lalu
menegaskan kiasan itu hanya untuk membuat pembacanya paham, oleh Hamzah
Fansûrî, laut dianalogikan sebagai Tuhan, sementara ombak adalah analogi untuk
makhluk. Lautan yang luas tidak terbatas itu dianalogikan dengan Tuhan yang Dzat
dan Kekuasaan-Nya tidak terbatas. Ombak adalah berbagai bentuk gelombang yang
senantiasa bergerak, tidak pernah tetap, dan beragam. Akan tetapi, sejatinya semua
ombak itu adalah lautan juga. Demikian juga semua makhluk yang berbeda-beda
bentuknya, beragam sifatnya, dan beragam warnanya, sejatinya adalah berasal dari
Tuhan473. Hamzah Fansûrî menulis:
“Ya’ni pada sekalian jalan, dan dimithalkan ombak-ombaknya penuh [pada]
sekalian jalan. Barang kita liha, zahir atau batin, sekalian-nya lenyap-ombak
jug. Ya’ni laut tiada bercerai dengan ombaknya, ombak [pun] tiada bercerai
469 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”, 236. 470 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”, 275. 471 Benny Baskara, Islam Bajo: Agama Orang Laut, (Pamulang: Javanica, 2016), 9–
10. 472 Drewes dan Brakel, The Poems of Ḥamzah Fansûrî…, 5–6. 473 Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri…, 153–154.
116
dengan laut. Demikian lagi Allah Subhanahu wa Ta’ala tiada bercerai dengan
‘alam.”474
Tidak kalah penting, analogi laut dan ombak adalah untuk menunjukkan bahwa
Tuhan dan makhluk tidak terpisahkan. Laut dan ombak keduanya bertaulan, misalnya
Tuhan dan hamba475. Dalam pernyataan tersebut, Hamzah Fansûrî ingin menegaskan
bahwa Tuhan itu hadir dalam setiap diri hamba. Wujûd hamba adalah dari wujûd
Tuhan. Dengan demikian, makhluk-makhluk itu bukan ketiadaan dan bukan juga
Tuhan, tetapi Tuhan hadir pada hamba dengan memberikan wujûd.
Bahr amiq atau laut yang dalam adalah analogi untuk eksistensi Tuhan yang
tidak terjangkau. Seperti lautan yang tidak terjamah oleh manusia, demikianlah
kiranya Tuhan dalam gambaran Hamzah Fansûrî. Pada masa itu, laut memang hanya
dapat diarungi. Tidak ada kemampuan manusia untuk menyelam ke dalam lautan.
Pada masa itu, manusia belum mampu mengetahui rahasia-rahasia di dalam laut.
Menyelam ke dalam lautan, baru mampu dilakukan manusia setelah teknologi
berkembang pesat pada masa yang jauh setelah Hamzah Fansûrî. Lagi pula, hingga
hari ini, baru sebagian kecil kedalaman laut yang mampu dijangkau manusia.
Tuhan itu dianalogikan dengan laut karena kedalaman dan rahasia laut tidak
akan pernah mampu dipahami manusia secara tuntas. Manusia hanya dapat melihat
laut melalui ombaknya saja. Laut juga menjadi analogi ilahiah yang perlu diselam
oleh pesuluk. Maka dalam syairnya, Hamzah Fansûrî menganalogikan pesuluk pada
tingkat tinggi sebagai ikan gajah mina yang hidup di laut yang dalam. Sementara
pesuluk pada tingkatan rendah dianalogikan seperti ikan tongkol yang menyelamnya
belum terlalu dalam.
10. Analogi-analogi Sekunder sebagai Berbagai Penjelasan Wujudiah
Buah, biji, cermin, manusia, sungai, batu, dan besi adalah analogi-analogi yang
digolongkan sebagai analogi sekunder. Analogi-analogi ini juga sangat tepat
dugunakan dalam menjelaskan tema metafisika tertentu dalam Wujudiah Hamzah
Fansûrî. Analogi-analogi itu digunakan dalam menjelaskan konsep-konsep
metafisika rumit bagi masyarakat Melayu. Berbeda dengan Ibn ‘Arabi yang
menjelaskan Wujudiah secara rumit, ketika ingin menjelaskan tentang bahwa Allah
itu Kekal (Qadîm), tidak memiliki permulaan sehingga tidak berkonsekuensi pada
keberakhiran, Hamzah Fansûrî menggunakan buah sebagai analoginya. Penggunaan
buah sebagai analogi karena umumnya buah itu berbentuk bundar. Pada buah bundar
tidak dapat ditunjuk mana awal dan mana akhir. Buah yang bundar itu tidak memiliki
awal dan tidak memiliki titik akhir. Hal itu tentu sangat mudah dipahami seluruh
lapisan masyarakat. Itulah yang digunakan Hamzah Fansûrî untuk menjelaskan
bahwa Tuhan itu Qadîm. Maksudnya adalah, Tuhan itu telah ada tanpa batas awal
dan tidak akan berakhir.
474 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 271 475 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 154.
117
“Adapun kata Ahlu’l-Kashf QadimNya itu mithal [suatu] buah [yang] buntar;
tiada berhujung dan tiada berpuhun, tiada permulaan dan tiada
berkesudahan, tiada di tengah dan tiada tepinya, dan tiada hadapan dan tiada
belakangnya, tiada kiri dan tiada kanan, tiada atas dan tiada bawahnya.”476
Analogi sederhana itu menunjukkan akurasi dan efektivitas objek analogi yang
digunakan. Padahal, dalam karya Mullâ Sadâ dan Ibn ‘Arabî misalnya, untuk
menjelaskan tentang Qadîm, membutuhkan penjelasan yang sangat panjang dan
rumit. Alih-alih memuaskan, malah berpeluang menghadirkan kebingungan. Masalah
ini biasanya muncul dalam karya-karya yang melakukan penalaran setelah
sebelumnya memiliki justifikasi.
Qadîm itu menjadi sulit dijelaskan dalam perspektif doktrin dan filosofis.
Sementara sufi adalah mereka yang menerima pengetahuan itu secara presentasional.
Mereka mengalami, bukan mempelajari konsep semata sehingga penjelasan mereka
menjadi lebih mudah dipahami. Apalagi dengan memilih menggunakan analogi yang
akurat untuk menjelaskannya.
Sebagai negara tropis, Kepulauan Indonesia telah lama menghasilkan aneka
jenis buah. Bahkan, keberagaman buah-buahan di kepulauan Indonesia dapat
dikatakan adalah yang paling lengkap. Tidak seperti daerah-daerah lain yang alamnya
jauh lebih tandus atau lebih dingin, Indonesia memiliki iklim tropis sehingga buah-
buahan yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Bahkan, buah-buahan tertentu di
Indonesia tentunya telah lama menjadi komoditas ekspor bersama rempah-rempah.
Hal ini tentu saja membuat analogi Hamzah Fansûrî tentang buah, khususnya buah
bundar menjadi sangat mudah dipahami masyarakat.
Debat tentang ilmu Tuhan memang dimulai oleh mutakallimîn dan filosof.
Filosof menawarkan solusi “materi primer” atau maddah al-ulâ sebagai suatu
kandungan potensi segenap wujûd selain Wajib Al-Wujûd bî Nafsihî. Sementara
skema itu menginspirasi ‘irfân dalam membahas konsep 'ayan tsabitah. Dalam 'ayan
tsabitah telah terkandung semua potensi atau sumber segala alam semesta. Hal ini
digambarkan seperti biji yang mengandung potensi keseluruhan pohon dari akar,
batang, cabang, ranting, hingga buahnya477.
“Adapun tamthil perbendaharaan itu seperti puhun kayu; sipuhun dalam
bijinya. Biji itu perbendaharaan. Puhun kayu yang dalamnya itu isi
perbendaharaan tersembunyi dengan lengkapnya: akarnya, dengan
batangnya, dengan chabangnya, dengan dahannya, dengan rantingnya,
dengan daunnya, dengan bunganya, dengan buahnya- sekalian lengkap di
dalam biji sebiji itu. Maka biji itu hendak mengeluarkan tumbuh puhun kayu
itu daripada dirinya di tengah padang yang mahaluas.”478
Analogi biji tentunya sangat akurat digunakan di samping juga sangat dekat
dengan masyarakat. Bagaimana ilmu Tuhan itu sebenarnya adalah suatu ketetapan
476 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 240. 477 Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri…, 132. 478 Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri…, 246.
118
yang mengandung seluruh potensi makhluk untuk beraktualitas. Dalam hal ini,
Hamzah Fansûrî telah mengajarkan bagaimana sebenarnya sifat Ilmu Tuhan, sifat
makhluk-makhluk sebelum mengaktual, dan menyanggah pandangan mutakallimîn.
Biji juga dianalogikan dengan bagaimana Sifat ‘Alim Bâsîth yang sifatnya
tetap. Lalu, menjadi bergerak menjadi pohon yang bergerak dari bijinya sebagaimana
‘Alim teraktualisasi melalui Ma’lûm hingga menghasilkan ilmu yang mengandung
potensi perubahan.
“Wujûd ‘alam pun dengan demikian lagi dengan Wujûd Allah-esa; karena
‘alam tiada berwujûd sendirinya. Sungguhpun pada zahirnya ada ia berwujûd,
tetapi wahmi juga, bukan wujûd haqiqi; seperti bayang-bayang dalam
chermin, rupanya ada hakikatnya tiada.”479
Alam semesta dalam ajaran Hamzah Fansûrî adalah pengetahuan Tuhan.
Pengetahuan Tuhan itu tetap. Ketetapan pengetahuan itu telah terkandung dalam
'ayan tsabitah. Pengetahuan tersebut dapat diraih ‘urafâ dalam pengetahuan
presentasi. Hadis qudsi berbunyi, "Aku adalah perbendaharaan tersembunyi, maka
aku ingin dikenal, sehingga kuciptakan semesta." Maksudnya adalah alam semesta
ini adalah pengetahuan Tuhan (ma'lûm). Pengetahuan itu berada dalam ilmu Tuhan
sehingga alam semesta adalah berada dalam ilmu Tuhan480.
Untuk membuat ‘ayân al-tsabîtah sebagai suatu sistem metafisika yang tinggi
menjadi sangat mudah dipahami, Hamzah Fansûrî menganalogikannya dengan biji.
Karena ‘ayan tzabitah adalah perbendaharaan tersembunyi (kanzân makhfiyyân),
sebagaimana bunyi sebuah Hadits Qudsi: “kuntû kanzan makfiyyan fa ahbabtû an
‘urafâ”, yakni Haqq Ta’âlâ menyatakan bahwa keadaannya adalah perbendaharaan
tersebunyi. Hamzah Fansûrî Menggambarkan:
“Biji itu perbendaharaan. Puhun kayu yang dalamnya itu isi perbendaharaan
tersembunyi dengan lengkapnya: akarnya, dengan batangnya, dengan
chabangnya, dengan dahannya, dengan rantingnya, dengan daunnya, dengan
bunganya, dengan buahnya- sekalian lengkap didalam biji sebiji itu.”481
Pada biji telah terkandung segala potensialitas pohon, seperti akarnya,
batangnya, cabangnya, dahannya, daunnya, rantingnya, dan buahnya untuk
menjelma. Maka biji itu hendak mengeluarkan tumbuh puhun kayu itu daripada
dirinya di tengah padang yang maha luas.482 Biji yang menjadi analogi ‘ayân al-
tsabîtah adalah objek pengetahuan Haqq Ta’âlâ yang menyatu dengan subjeknya. Ia
menjelma dengan kûn sebagai bentuk ‘Amr dari Haqq Ta’âlâ. Adapun ‘Amr itu
terjadi berkat kehendak-Nya. Sebagaimana skema Nama-nama dalam sistem Ibn
‘Arabî , Kehendak berlaku karena adanya ‘Ilmû, ‘Ilmû berlaku karena adanya Haya’
479 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 282. 480 Chittick, William C., The Sufi Doctrine of Rumi, (Indiana: World Wisdom, Inc.,
2005), 12. 481 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 246. 482 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 246.
119
dan Haya’ berlaku karena Wujûd. Karena itu, semua itu terjadi sebagai satu kesatuan
wujûd, termasuk ketika kanzân makfî sebagai biji itu tadi sebagai objek pengetahuan
berkata pada dirinya, “Akulah perbendaharaan tersembunyi, maka aku cinta
diketahui,” sehingga menjelmalah alam semesta. Dengan demikian, berseberangan
dengan mutakallimîn dan bersesuaian dengan para filosof, ‘urafa, termasuk Hamzah
Fansûrî mengatakan bahwa ketika Haqq Ta’âlâ berkata kûn, perkataan itu dituju pada
sesuatu yang memang telah ada, bukan berkata pada ketiadaan. Hamzah Fansûrî
menjelaskan483:
“Karena itu maka kata Ahlul Suluk makna kûn itu kepada ma’lumat di dalam
Ilmu Allah yang sedia mawjud. Tetapi kepada ‘ulama (mutakallimîn) ma’lumat
itu (yakni sasaran perkataan ‘kun’), tiada mawjûd, hadits (baharu) datang
tatkala ia pandang-pandang Diri-Nya”484.
Bagi mutakallimîn, alam semesta berasal dari tiada, lalu menjadi ada (baharu).
Bagi penganut wujudiah meskipun secara zahir alam semesta belum menjelma, ia
telah ada secara batin (yakni kanzân makfî) pada ‘ayân al-tsabîtah. Pandangan ‘urafâ
ini sesuai dengan pandangan filosof, yakni Wajîb al-Wujûd menjadikan alam semesta
dari wujûd yang lain sebelumnya. Demikianlah seumpamanya biji itu berkata akulah
perbendaharaan tersembunyi485. Pada hadis qudsi, Al-Haqq juga menganalogikan
Diri-Nya sebagai “perbendaharaan tersembunyi”, yaitu kanzân makfiyyan. Adapun
bunyi hadis qudsi dimaksud adalah, “Kuntû kanzân makfiyyan fâ ahbabtû an ‘urafâ”.
Analogi bagi “perbendaharaan tersembunyi” oleh Hamzah Fansûrî adalah “biji”486.
Analogi ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam pandangan sufi,
segala wujûd selain Al-Haqq telah mengada bersama-Nya sehingga wujûd selain Al-
Haqq bukanlah wujûd baharu. Analogi ini dipakai untuk menyanggah argumentasi
mutakallimîn yang menyatakan bahwa makhlûqat berasal dari ketiadaan487. Biji yang
dimaksud untuk menyebutkannya sebagai benih yang dapat menumbuhkan pohonnya
kembali. Biji adalah bagian dari buah yang umumnya di dalam dan menjadi inti buah.
Dari biji dapat disemai menjadi buah karena pada biji tersebut telah terkandung
totalitas buah. Penunjukan biji sebagai analogi menjadi akurat karena mustahil
membayangkan keterpisahan suatu tumbuhan dari sumbernya, yakni biji. Analogi ini
diakui Hamzah Fansûrî diambilnya dari Ibn ‘Arabî488.
Biji juga dianalogikan dengan bagaimana Sifat ‘Alîm Haqq Ta’âlâ yang tetap.
Lalu, menjadi bergerak menjadi pohon yang bergerak dari bijinya sebagaimana ‘Alîm
teraktualisasi melalui Ma’lûm hingga menghasilkan ‘Ilmû yang mengandung potensi
perubahan.
483 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 246. 484 Al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansûrî.., 247. 485 Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri…, 132. 486 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 246. 487 Israr Ahmad Khan, “Identifying Entity and Attributes of God: An Islamic
Perspective Mengenal Pasti Entiti Dan Sifat-Sifat Allah: Satu Perspektif Islam.” Journal of
Islam in Asia (E-ISSN: 2289-8077) 13, no. 1 (July 19, 2016), 248-264. 488 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 253.
120
Dalam gambaran Hamzah Fansûrî, alam semesta adalah ilmu Tuhan. Sebab
itulah, ajaran Hamzah Fansûrî dan sealiran dengannya disebut Wujudiah489. Allah
adalah yang mengetahui. Dia juga yang diketahui dan dia juga aktivitas
pengetahuan. Hal ini karena segenap alam adalah pengetahuan Allah, sebagaimana
Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 115:
واسع عليم ان للاه المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه للاه ولله
“Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap di sanalah
wajah Allah. Sungguh, Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”
Meskipun berada dalam ilmu Tuhan, ilmu itu mengaktual sehingga menjadi
alam semesta. Meskipun terkadang alam semesta disebut bayang-bayang, tetapi
sejatinya alam semesta memiliki wujûd, bukan ketiadaan mutlak. Hal yang
membingungkan adalah karena terkadang Hamzah Fansûrî menyebut alam semesta
seperti bayangan di dalam cermin490. Bayangan di dalam cermin sifatnya adalah tiada.
Akan tetapi, perspektif yang akurat untuk memaknai makna kondisi alam semesta
atau makhluk-makhluk sebagai analogi bayangan di dalam cermin adalah, pertama
sifat kebergantungannya secara mutlak kepada empunya bayangan sebagaimana
kebergantungan mutlak makhluk-makhluk kepada Tuhan. Kedua, keberadaan
bayangan adalah karena keberadaan empunya bayangan. Maknanya adalah,
bayangan menjadi ada karena ada-nya empunya bayangan. Demikian juga makhluk-
makhluk memiliki wujûd karena diberikan wujûd oleh Tuhan. Ajaran Wujudiah atau
Wahdah al-Wujûd bukan skeptisme yang menafikan keberadaan alam semesta.
Iktikad Wujudiah mengatakan alam semesta itu majasi seperti eksistensi bayangan di
dalam cermin, tetapi bukan menganggapnya tiada karena pada banyak kesempatan,
Hamzah Fansûrî mengatakan bahwa makhluk-makhluk memiliki wujûd (bukan
ketiadaan) yang diberikan Tuhan sekaligus wujûd makhluk tidak komposit dengan
wujûd Tuhan491.
Keunikan ajaran Hamzah Fansûrî adalah mampu mengomunikasikan ajaran
Wujudiah yang berat dalam bahasa yang indah dan menggunakan analogi yang
mudah dipahami. Untuk menggambarkan kondisi makhluk, Hamzah Fansûrî
menganalogikannya seperti bayangan di dalam cermin. Meskipun tidak dapat
dipastikan apakah di rumah semua masyarakat Melayu pada masa itu memiliki
cermin, tetapi hampir dapat dipastikan semua masyarakat dapat mengenal apa itu
cermin dan mengetahui bahwa cermin memantulkan bayangan. Lagi pula, mengingat
pada masa itu sebagian masyarakat tinggal dalam satu rumah besar yang disebut
rumah adat yang dihuni beberapa keluarga kecil meskipun tidak termasuk keluarga
petinggi, tetapi besar kemungkinan setiap rumah adat memiliki cermin. Maka dari
itu, tidak dapat diragukan bahwa semua masyarakat waktu itu dapat mengenal cermin
489 Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri…, 154. 490 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…,, 282. 491 Misalnya ketika Hamzah Fansûrî mengatakan bahwa Tuhan dan hamba tidak
terpisah sebagaimana laut dan ombak tiada bercerai. Lihat, Doorenbos, De Gefchriften van
Hamzah Pansoeri…, 153.
121
dan mengetahui bahwa cermin memantulkan bayangan. Dalam hal ini, cermin yang
dimaksud dalam analogi sufi berbeda dengan cermin yang digunakan hari ini. Pada
masa lalu, cermin dibuat dari logam yag digosok. Makin bagus digosok, pantulannya
makin jelas.
Sebagaimana bayangan yang muncul dalam cermin, begitulah diri manusia dan
segenap makhluk lainnya. Bayang-bayang di dalam cermin memang terkesan
memiliki wujûd. Akan tetapi, sebenarnya wujûd tersebut tidak independen, hanya
wahmî. Akan tetapi, makna wahmî dalam Wujudiah bukan berarti ketiadaan,
melainkan nyata untuk dirinya (thing by it self, nafs al-‘amr)492. Dalam hal ini, status
eksistensi alam semesta dapat dipahami dengan mudah melalui analogi bayangan di
dalam cermin. Eksistensi bayangan di dalam cermin tidak independen. Dikatakan
tidak ada, ia ada, dikatakan ada, keberadaannya bergantung secara mutlak pada
keberadaan empunya bayangan. Dengan analogi ini, hubungan antara Tuhan dan
makhluk menjadi mudah dipahami. Hubungannya adalah seperti seseorang yang
berdiri di hadapan cermin dan bayangan di dalam cermin. Makhluk-makhluk seperti
bayangan di dalam cermin493. Sementara empunya bayangan dianalogikan seperti
wujûd Tuhan yang independen, memberikan wujûd, dan tempat bergantungnya wujûd
alam secara mutlak.
Mungkin analogi cermin menjadi lebih mudah dipahami untuk hari ini yang
memang semua orang memiliki cermin, bahkan dibawa ke mana-mana. Di mana pun,
cermin dapat ditemukan. Namun sayangnya, manusia modern meskipun memiliki
banyak fasilitas, miskin renungan dan refleksi diri. Bahkan, manusia hari ini hidup
seperti orang yang sedang merenung, tidak dapat mengenali dirinya dan miskin
pengetahuan terhadap sekitarnya meskipun fenomena di sekitarnya makin majemuk.
Kalaupun dikenali, permukaannya saja. Pengenalan diri dan pendalaman terhadap
kedirian individu yang lain pada zaman modern baru dimulai kembali oleh para
filosof eksistensialisme, seperti Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jean-Paul
Sartre, Albert Camus, dan beberapa tokoh eksistensialis lainnya. Padahal, prinsip
mengenal diri telah menjadi bagian dari diskursus penting dalam dunia Islam,
khususnya yang dipelopori oleh para sufi Wujudiah, termasuk Hamzah Fansûrî494.
Tidak hanya pengenalan diri, bahkan kedirian manusia dalam ajaran Hamzah
Fansûrî telah digunakan sebagai bagian dari analogi untuk membuat ajarannya
menjadi mudah dipahami. Manusia tidak lebih dikenal, kecuali melalui peran dan
fungsinya. Memang kepada seseorang kita dapat mengetahui ciri-ciri fisiknya, tetapi
ciri-ciri fisik tidak lebih dapat membantu membuat kenal kepada seseorang
dibandingkan profesinya. Misalnya, seseorang bernama Muhammad memiliki ciri-
ciri fisik demikian dan demikian. Akan tetapi, secara lebih luas dia dikenal melalui
sifatnya, apakah dia orangnya santun, penyayang, dan lemah lembut. Sifat-sifat itu
juga hanya dapat dikenal atau dirasakan secara terbatas. Untuk lebih luasnya,
492 Jabir, Wahdah Al-Wujûd Ibn ‘Arabî Dan Filsafat Wujûd Mulla Sadrâ, 18. 493 Ismail Fahmi Arrauf Nasution, “Termination OF Wahdah al-Wujûd In Islamic
Civilization In Aceh: Critical Analysis of Ithaf Ad-Dhaki, The Works of Ibrahim Kurani,”
ADDIN 11, no. 2 (August 1, 2017): 401,
http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/view/3356. 494 Epicurus, Seni Berbahagia, (Yogyakarta: BasaBasi, 2019), 33.
122
seseorang dikenal melalui profesinya. Apakah dia seorang penulis atau seorang
pedagang. Melalui profesinya seseorang dapat dikenal lebih luas hingga ke tempat-
tempat yang belum melihat ciri-ciri fisiknya dan belum merasakan sifatnya495.
Hamzah Fansûrî menggunakan nama Muhammad untuk mencontohkan
pengenalan melalui profesi karena nama tersebut sangat sering diberikan para orang
tua kepada anaknya di dunia Melayu. Hamzah Fansûrî menggunakan seorang sosok
manusia untuk menggambarkan hubungan antara Tuhan dan sifat-sifatnya. Kita
mengenal Tuhan sebagai Mahakaya, Maha Memberi, dan sebagainya. Melalui Sifat-
Sifat-Nya itu Tuhan dikenal. Bahkan, dalam pembukaan Asrâr, Hamzah Fansûrî telah
menegaskan bahwa sifat-sifat itu dipredikasikan sesuai dengan bagaimana kita
mengenal496.
Seperti Muhammad, apabila dia menulis, dia disebut penulis. Apabila dia
berniaga disebut saudagar. Sebagai penulis dan sebagai saudagar adalah sifat yang
disematkan kepada Muhammad setelah meninjau profesi atau perbuatannya.
Demikian juga Tuhan disebut al-Ghanî dan disebut al-Rahman karena demikian
'amr-Nya. Penulis dan saudagar itu tidak memiliki eksistensi yang terpisah dari
Muhammad. Penulis dan saudagar adalah sifat yang dibuat untuk Muhammad.
Demikian juga al-Ghanî dan al-Rahman adalah sifat untuk Tuhan. Inilah yang ingin
dijelaskan Hamzah Fansûrî dalam menjadikan manusia sebagai analogi ajarannya.
Tentunya analogi manusia dan sifatnya untuk menjelaskan hubungan Tuhan dan
sifatnya sangat mudah dipahami. Bahwasanya sifat dan Zat Tuhan itu bukan dualitas
eksistensi sebagaimana anggapan sebagian mutakallimîn. Hamzah Fansûrî hendak
mengoreksi pandangan tersebut. Hamzah Fansûrî menggunakan analogi yang sangat
sederhana sehingga sangat mudah dipahami.
Analogi manusia digunakan juga untuk menggambarkan hubungan Tuhan dan
makhluk. Tuhan dianalogikan dengan raja. Seorang raja tentu bersyarat pada
kekuasaan. Apabila tidak memiliki kekuasaan, batallah ia menjadi raja. Demikian
juga alam semesta ini adalah aktualitas dari ilmu Tuhan. Dengan adanya alam, Tuhan
disebut dengan 'Alim. Sebenarnya dalam menjelaskan persoalan ini, Hamzah Fansûrî
sedang menjelaskan relasi kausal yang menjadi pembahasan dalam filsafat. Terdapat
konsep-konsep yang tidak berdiri sendiri, tetapi ia meniscayakan relasi. Misalnya,
konsep “ayah” meniscayakan relasinya dengan konsep “anak”. Demikian juga konsep
raja meniscayakan keberadaan “yang dirajai”. Namun dengan menggunakan frasa
sederhana dengan cara penganalogian status raja, Hamzah Fansûrî dapat dikatakan
berhasil menyederhanakan persoalan filosofis yang sulit497.
Meskipun pada masa itu jenis-jenis profesi manusia belum sebanyak hari ini,
bukan berarti profesi-profesi waktu itu terbatas pada saudagar, petani, dan pelaut saja.
Terdapat juga berbagai profesi lainnya, seperti perajin, baik itu pandai besi, pandai
kayu, pandai tenun, maupun utus. Utus adalah salah satu profesi penting yang sangat
495 Subahri, “Aktualisasi Akhlak Dalam Pendidikan,” Islamuna: Jurnal Studi Islam 2,
no. 2 (December 5, 2015): 167,
http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/islamuna/article/view/660. 496 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 239–240 Bandingkan, Doorenbos, De Gefchriften
van Hamzah Pansoeri…, 124–125. 497 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 253–255.
123
dibutuhkan masyarakat. Keindahan bangunan-bangunan tradisional, perahu-perahu
yang indah, pembuatannya dipimpin oleh seorang yang sangat tinggi daya
imajinasinya, terampil tangannya, dan dia adalah pengamat yang rinci. Semua orang
mengenal utus. Dengan demikian, semua orang dapat paham bahwa sebelum suatu
mahakarya dibangun, tentu gambarnya yang merupakan sumber potensi aktualitas
bangunan telah sempurna dalam imajinasi seorang utus atau bahasa sekarang disebut
arsitek498.
Tuhan sebagai al-'Alîm juga dianalogikan dengan seorang utus (arsitek,
tukang). Alam dianalogikan dengan arsitektur. Kukuh, rapi, dan indah sebuah
arsitektur menunjukkan kepiawaian sang arsitek. Sebagaimana sebuah bangunan
yang telah eksis sebagai potensialitas dalam ilmu tukang sebelum bangunan
didirikan, demikian juga segenap alam semesta telah eksis dalam ilmu Tuhan sebelum
mengaktual. Tentunya analogi ini sangat mudah dipahami karena hampir di setiap
dusun terdapat tukang bangunan yang disebut utus. Setiap orang dapat memahami
bahwa sebelum dikerjakan, sebuah bangunan telah eksis sebagai suatu potensialitas
dalam pengetahuan sang utus. Sebuah bangunan adalah aktualitas dari ilmu sang utus.
Demikian analogi yang dibuat untuk menjelaskan bahwa alam semesta adalah
aktualitas ilmu Tuhan.
Imajinasi utus sebagai potensialitas yang tetap, lalu mengaktual dalam bentuk
bangunan juga sangat tepat sebagai analogi kanzân makfî, yakni perbendaharaan
tersembunyi di lâwh mahfudz. Ketika yang di lâwh mahfudz teraktual dalam bentuk
partikularitas terpersepsikan, itu seperti dibangunnya rumah secara bertahap.
Demikianlah bagaimana Hamzah Fansûrî benar-benar dapat menggunakan analogi
yang mudah dipahami masyarakat499.
Analogi imajinasi utus dapat berlaku untuk semua jenis bangunan dan juga
kendaraan penting bagi masyarakat, seperti perahu. Sebagai masyarakat yang
umumnya berdomisili di pesisir atau sangat dekat dengan sungai, perahu tentunya
dikenal oleh semua masyarakat. Selain menjadikan jasad manusia sebagai objek
analogi, jasad manusia juga dijadikan Hamzah Fansûrî sebagai acuan analogi.
Sementara objek analoginya adalah perahu. Sebagai makhluk Ilahiah, manusia harus
mempersiapkan bekal amal kebaikan di dunia sebagaimana mempersiapkan segala
perbekalan ke dalam perahu dalam rangka mengarungi lautan. Perjalanan hidup
manusia di alam spiritual dianalogikan dengan perahu yang berlayar mengarungi
samudra. Setiap kapal perlu mengisi perbekalan untuk berlayar. Tidak hanya kapal-
kapal dagang yang mengarungi samudera, kapal-kapal nelayan juga perlu melakukan
hal yang sama. Pelayaran dan masyarakat Indonesia, khususnya di Aceh hampir tidak
dapat dipisahkan500.
498 Chittick, The Self-Disclosure of God: Principles of Ibn Al-’Arabi’s Cosmology…,
187. 499 Analogi ini pernah dipakai Ibn ’Arabi untuk menjelaskan persoalan yang sama.
Tetapi Ibn ’Arabî melakukannya dengan cara yang rumit. Chittick, The Self-Disclosure of
God: Principles of Ibn Al-’Arabi’s Cosmology, 187. 500 Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, “A Study of Panglima La’ōt: An ‘Adat
Institution in Aceh,” Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies 55, no. 1 (June 26, 2017): 155–
188, http://aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/55107.
124
Fansur dan bandar-bandar lainnya adalah tempat transit kapal-kapal besar.
Masyarakat Melayu waktu itu mendominasi kota-kota pelabuhan sehingga mereka
menjadi sangat dekat dengan kapal. Dengan demikian, analogi diri manusia sebagai
perahu sangat mudah dipahami dan dihayati. Bahkan, Hamzah Fansûrî menjadikan
perahu sebagai analogi diri manusia yang harus mempersiapkan bekal diri untuk
mengarungi perjalanan jiwa yang terus berlanjut sejak awal bait puisinya:
Hai muda arif budiman
Hasilkan kemudi dengan pedoman
Alat perahumu juga kerjakan
Di sanalah jalan membetuli insan
Perteguh juga alat perahumu
Hasilkan bekal air dan kayu
Dayung pengayuh taruh di situ
Supaya laju perahumu itu501
Kepekaan Hamzah Fansûrî tidak hanya pada aspek sosiokultural, tetapi juga
pada aspek lingkungan atau kondisi geografis masyarakat Melayu khususnya dan
masyarakat Indonesia umumnya502. Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki sangat
banyak sungai, baik yang besar maupun kecil. Pada masa lalu, jumlah sungai jauh
lebih banyak daripada hari ini. Itu terjadi akibat perubahan iklim dan campur tangan
manusia. Sungai adalah sesuatu yang sangat dekat dengan masyarakat503.
Hamzah Fansûrî menggunakan aliran sungai sebagai analogi kesatuan
hubungan antara Tuhan dan makhluk. Bahwasanya Tuhan dan makhluk bukanlah
dualitas sebagaimana dipahami mutakallimîn. Tuhan dan makhluk adalah satu
kesatuan utuh persis seperti aliran sungai. Tidak ada terputus-putus pada aliran
sungai504. Demikian juga makhluk mendapatkan wujûd dari Tuhan. Wujûd itu
bersambung dari wujûd Tuhan pada wujûd makhluk505.
Hamzah Fansûrî menggunakan beberapa sisi pandang air sebagai analogi bagi
beberapa sisi ajarannya. Tuhan yang Satu sebagai sumber segala makhluk
501 Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri…, 16. 502 Anthony Reid, “ Understanding Melayu (Malay) as a Source of Diverse Modern
Identities ,” Journal of Southeast Asian Studies (2001). 503 Krisis ekologi semakin parah terjadi di Aceh akibat pengabaian para agen sosial.
Lihat, Ismail Fahmi Arrauf Nasution dan Miswari, “Al-‘Ulamā’ Warathat Al-Anbiyā’:
Modernity and Nurture of Authority in Aceh Society,” Jurnal Theologia 30, no. 2 (December
23, 2019): 197, http://journal.walisongo.ac.id/index.php/teologia/article/view/3845. 504 Fansûrî, “Syarâb Al-Asyiqîn,”…, 265 Bandingkan, Doorenbos, De Gefchriften van
Hamzah Pansoeri…, 147. 505 Hamzah Fansûrî ingin menegaskan bahwa alam semestaitu adalah berwujud, tetapi
bukan pada aksiden-aksiden, melainkan pada wujud, karena pada aksiden adalah bayangan.
Hal ini dikuatkan dengan pernyataan para sahabat yang pada alam melihat wujud: Abubakar
(sebelum), Usman (setelah), Usman (beserta), Ali (dalam) mahiyah. Fansûrî, “Syarâb Al-
Asyiqîn,”…, 265–266 Bandingkan, ; Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri…,
148.
125
dianalogikan dengan air yang menjadi sumber kehidupan segala macam tumbuhan.
Meskipun tumbuh berbagai bentuk, berbagai warna, dan berbagai jenis tumbuhan,
asalnya tetap dari air. Demikian juga alam semesta yang beraneka ragam berasal dari
Tuhan yang satu.
“Karena yang dinamai laut itu air, apabila laut itu timbul bernama halun;
apabila naik berhimpun di udara bernama awan; apabila jatuh bertitik di
udara bernama hujan; apabila hilir di bumi bernama sungai; apabila pulang
ke laut hukumnya.”506
Pembahasan tersebut konteksnya adalah menganalogikan Bâsîth sebagai ‘Alîm
yang dianalogikan dengan air. Sementara Ma’lûm-Nya dianalogikan dengan
keberagaman yang berasal dari satu. Dalam konteks ini, Dia sebagai yang dibagi
bernama Qâsîm, sekaligus Dia sebagai yang dibagi bernama Maqsûm. Seumpama
laut adalah yang dibagi, sementara bagiannya seperti ombak. Sejatinya ombak-ombak
itu laut. Demikian sejatinya Qâsîm itu adalah Maqsûm. Adapun munculnya ombak
adalah karena Syu’un-nya, yakni karena perbuatan-Nya507.
Meskipun Timur Tengah dan Afrika adalah negeri-negeri yang tandus, bukan
berarti masyarakatnya tidak mengenal air. Air adalah sumber kehidupan manusia
sehingga semua orang dapat dengan mudah mengenalnya meskipun di beberapa
negara banyak orang tidak dapat mengaksesnya dengan mudah. Air adalah sesuatu
yang sangat dekat dengan manusia sehingga sangat lumrah Hamzah Fansûrî juga
menggunakan air sebagai analogi ajarannya. Kepulauan Indonesia sebagai negara
tropis, tumbuh berbagai jenis pohon sangat menginspirasi Hamzah Fansûrî
menggunakan analogi tersebut. Meskipun sufi Timur Tengah telah lebih dahulu
menggunakan analogi air, analogi tersebut menjadi lebih relevan dipakai bagi
masyarakat Indonesia karena tumbuh sangat banyak jenis tumbuhan508.
Demikian pula ketika analogi air itu digunakan untuk menjelaskan sesuatu
yang sangat berat, yaitu tentang bagaimana dari Tuhan yang satu memunculkan
keberagaman. Persoalan ini telah menjadi diskursus yang rumit dan serius sepanjang
sejarah pemikiran manusia sejak filsafat Hindu, Yunani Klasik, mutakallimîn, dan
filsafat Islam. Sementara oleh Hamzah Fansûrî menjadi sangat sederhana dengan
analogi yang digunakan. Dalam konteks ini, Hamzah Fansûrî menggambarkan air
yang merupakan jenis yang satu dapat menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan dari
air tersebut. Tanpa air, tumbuhan-tumbuhan yang beragam tidak dapat tumbuh.
Berbeda dengan negara-negara yang tandus dan gersang, analogi untuk air yang
menumbuhkan berbagai jenis tanaman sangat sesuai untuk wilayah yang tropis
seperti Indonesia. Dengan demikian, analogi tersebut menjadi sangat mudah
dipahami oleh masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi ajaran Hamzah
Fansûrî509.
506 Fansûrî, “Syarâb Al-Asyiqîn,”…, 265. 507 Fansûrî, “Syarâb Al-Asyiqîn,”…, 265. 508 Jatna Supriatna, Melestarikan Alam Indonesia, (Jakarta: Buku Obor, 2008), 43. 509 Drewes dan Brakel, The Poems of Ḥamzah Fansûrî…, 3–4.
126
Dalam konteks analogi air, Tuhan Maha Mengetahui disebut dengan Qasîm,
yakni yang dibagi atau dipisahkan atau sesuatu yang diseparasikan dengan
dianalogikan juga dengan air. Sementara realitas semesta sebagai bagian yang
dipisahkan disebut dengan maqsûm, yakni bagian. Qasîm adalah air, sementara
maqsûm menjadi berbagai nama sebagaimana beragamnya makhluk diseparasikan
nama-namanya dalam berbagai tinjauan kondisi. Air ketika di samudra disebut laut.
Ketika naik ke langit disebut awan. Ketika turun ke bumi disebut hujan. Ketika
mengalir di darat disebut sungai. Ketika kembali ke samudra disebut laut. Demikian
juga alam semesta menjadi berbagai bentuk dan berbagai jenis karena berbagai
kecenderungan esensi yang menampilkannya menjadi berbagai kondisi.
Sebagaimana sungai, laut, dan hujan juga adalah air, demikian juga wujûd sebenarnya
adalah realitas yang tunggal, menjadi beragam kondisi yang semuanya itu adalah air,
sebagaimana wujûd yang satu terdapat kemajemukan di dalamnya. Demikian
Hamzah Fansûrî ingin menegaskan bahwa makhluk-makhluk menjadi wujûd dengan
satu Wujûd meskipun kita memersepsikan kemajemukan.
Demikian sebenarnya keberagaman makhluk adalah bagian dari Tuhan.
Segenap makhluk menjadi beragam nama hanya dalam pengamatan. Sementara
hakikatnya adalah satu, yakni air, menjadi laut, menjadi awan, menjadi hujan,
menjadi sungai, dan kembali menjadi laut adalah pada sisi pengamatan saja510.
Sebenarnya analogi ini dapat ditambahkan dengan muara, yakni kondisi air
antara dari sungai menuju samudra. Akan tetapi, Hamzah Fansûrî tidak menggunakan
analogi tersebut. Mungkin karena istilah muara belum ada waktu itu. Mungkin juga
karena muara bukan sesuatu yang akrab dalam dunia masyarakat. Hal ini karena
biasanya muara merupakan lokasi yang titiknya jauh dari permukiman masyarakat
pada masa itu. Umumnya di Aceh dan negeri-negeri Melayu, muara menjadi bagian
dari habitat pohon bakau yang tidak menjadi perhatian masyarakat untuk dikunjungi.
Jadi, tidak begitu familier511.
Air juga dianalogikan dengan Tuhan sebagai perbendaharaan tersembunyi
(kânzan makfî) yang berkehendak untuk dikenali sehingga Dia menciptakan alam
semesta yang dianalogikan dengan buih. Buih adalah aktualitas air yang menjelma di
permukaan. Sementara sebenarnya buih-buih tersebut adalah aktualitas air dalam
beragam bentuk. Demikian juga Tuhan sebagai yang tersembunyi mengaktualkan
alam dalam aneka ragam bentuk. Tujuannya supaya manusia mengenal Tuhan
melalui alam semesta. Air juga dianalogikan dengan Tuhan, sementara buih
dianalogikan dengan pesuluk. Pesuluk itu adalah orang yang dianggap telah bersatu
dengan Tuhan. Karena itu, dirinya menjadi wadah Tuhan secara keseluruhan.
Aktualitasnya adalah aktualitas Tuhan512.
510 Al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansûrî…, 228. 511Aji Ali Akbar, et al., “Erosi Pantai, Ekosistem Hutan Bakau Dan Adaptasi
Masyarakat Terhadap Bencana Kerusakan Pantai Di Negara Tropis (Coastal Erosion,
Mangrove Ecosystems and Community Adaptation to Coastal Disasters in Tropical
Countries),” Jurnal Ilmu Lingkungan 15, no. 1 (May 13, 2017): 1,
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/view/12822. 512 Miswari, Filsafat Terakhir…, 47.
127
Selain air, benda alam yang sangat dekat dengan masyarakat tropis adalah batu.
Tidak seperti Timur Tengah dan Afrika yang mana batu umumnya diproduksi dari
pengeringan tanah atau bongkahan dan serpihan gunung, di negeri tropis seperti
Indonesia, batu sangat mudah di dapatkan melalui sungai. Di dalam timbunan tanah
juga terdapat banyak batu. Untuk itulah, analogi batu dalam konteks menjelaskan
ajaran Wujudiah menjadi sangat mudah dipahami.
Batu adalah analogi yang sangat sederhana untuk menggambarkan kehendak
manusia dalam hubungannya dengan kehendak Tuhan. Batu adalah benda yang
sangat dekat dengan kehidupan manusia. Batu dapat ditemukan di mana pun. Batu
dikenal siapa pun, bahkan hingga anak-anak. Batu di kampung-kampung sering
digunakan untuk melempari ternak yang masuk area terlarang. Batu digunakan untuk
mengusir monyet di kebun. Batu digunakan untuk mengusir burung yang mencoba
mencuri padi yang mulai menguning di sawah. Begitu tidak berdayanya batu-batu
dalam hubungannya dengan manusia yang melemparnya. Begitulah analogi makhluk.
Yang sama sekali tidak berdaya di hadapan Tuhan. Sebenarnya, hal ini dipercaya
dalam setiap tradisi spiritualitas513.
Batu juga dianalogikan dengan cara lain oleh Hamzah Fansûrî. Meskipun tidak
banyak yang memiliki, bahkan pada masa itu tidak semua orang pernah melihatnya,
tetapi semua orang mengetahui emas. Diketahui pula bawa sebenarnya sebongkah
emas di perut bumi itu jenisnya adalah batu. Emas dianalogikan dengan Tuhan.
Sementara batu dianalogikan dengan selain Tuhan. Apabila dalam suluk seseorang
masih melihat selain Tuhan, dia belum menyatu dengan Tuhan. Antara Tuhan sebagai
emas dan makhluk sebagai batu dalam analogi ini harus tidak ada dualitas lagi.
Karena apabila masih menerima dualitas, itu artinya masih belum bersatu (wasil).
Kebersatuan inilah yang disebut dengan makrifat; sebuah pengetahuan tertinggi514.
“Ya’ni tamthil emas [itu iaitu] Tuhan, dan matu [ia itu] hamba. Karena pada
penglihatan emas lain, matu lain. Tetapi emas tiada bercherai dengan matu,
dan matu tiada bercherai dengan emas’515
Analogi emas dan batu untuk menggambarkan apabila manusia masih melihat
batu pada emas, berarti dia belum mengalami fânâ. Sementara ketika hanya melihat
emas, berarti dia telah mengalami fânâ. Penekanan dalam konteks ini adalah
bagaimana manusia harus melenyapkan eksistensi dirinya yang hanya merupakan
bayangan, tidak nyata untuk dapat melihat Realitas yang Nyata yang dianalogikan
dengan emas.
Namun, fânâ yang lebih baik bagi Hamzah Fansûrî adalah seperti yang
dianalogikan dengan laron sebagai pesuluk dan api sebagai Bâsîth. Ketika laron telah
masuk api, ia benar-benar kehilangan dirinya. Kondisi fânâ yang digambarkan ini
menjadi semacam sebuah kritik bagi analogi fânâ yang dibuat Jalal al-Dîn Rûmî yang
513 Daniel Nugraha Tanusaputra, “Kerohanian Dan Pelayanan Seorang Hamba Tuhan,”
Veritas : Jurnal Teologi dan Pelayanan 14, no. 2 (October 1, 2013): 253–276,
https://ojs.seabs.ac.id/index.php/Veritas/article/view/281. 514 Fansûrî, “Syarâb Al-Asyiqîn,”…, 287–288. 515 Fansûrî, “Syarâb Al-Asyiqîn,”…, 287–288.
128
menganalogikan fânâ dengan meleburnya besi ke dalam api. Dalam kondisi tersebut,
besi mengaku dirinya api, tetapi sejatinya dualitas besi dan api masih ada.
Analogi yang lebih sederhana menggambarkan kondisi fânâ dalam suluk
adalah musnahnya laron ke dalam api. Dalam masyarakat pada masa itu, laron yang
selalu mendatangi api, lalu musnah terbakar ke dalamnya adalah pemandangan
sehari-hari masyarakat. Fenomena itu digunakan Hamzah Fansûrî sebagai analogi
pesuluk yang lenyap dalam Tuhan. Kedirian pesuluk harus benar-benar lenyap
sehingga mengetahui hakikat yang nyata, yakni Tuhan yang Tunggal516.
Sebagaimana tidak berdayanya batu bagi manusia menjadi analogi tidak
berdayanya manusia di hadapan kuasa dan kehendak Tuhan. Analogi besi dan tukang
besi juga digunakan untuk menjelaskan maksud yang sama. Tentu saja analogi besi
dan tukang besi digunakan karena itu sangat dekat dengan masyarakat. Hampir pada
setiap mukim di Aceh pada masa itu terdapat tukang besi. Pisau, parang, arit, cangkul,
dan senjata dipesan pada tukang besi. Masyarakat tentu sangat mengetahui bahwa
besi-besi sama sekali tidak berdaya di tangan tukang besi. Besi tunduk pada kehendak
tukang besi. Tukang besi berkuasa mutlak dalam membentuk besi. Demikian juga
ketika besi dianalogikan sebagai manusia dan tukang besi dianalogikan sebagai
Tuhan. Manusia dan semua makhluk benar-benar Tunduk pada ketetapan, kehendak,
dan kendali Tuhan517.
D. Pemaknaan Wujudiah Hamzah Fansûrî
Perkembangan ajaran Wujudiah dalam khazanah intelektual Islam
didayagunakan dengan baik oleh Hamzah Fansûrî untuk mengembangkan ajaran
tasawufnya. Uniknya, Hamzah Fansûrî mampu mengomunikasikan ajaran filosofis
yang rumit itu dalam budaya masyarakat Melayu yang memiliki tradisi keilmuan dan
budaya yang berbeda dengan konteks perkembangan ajaran Wujudiah di Timur
Tengah. Karya-karya Hamzah Fansûrî mengandung banyak sekali pesan kepada
manusia supaya menghindari kecenderungan duniawi. Hal ini dapat diduga karena
Hamzah Fansûrî melihat pada masanya, masyarakat terlalu sibuk dengan urusan
duniawi. Hamzah Fansûrî sangat sering mengingatkan supaya masyarakat tidak
terjebak oleh dunia dan kecenderungan mendekati penguasa. Karena memang pada
masa itu, dunia Melayu memiliki hubungan internasional yang baik. Perdagangan
berlangsung pesat. Manusia hidup pada zaman kosmopolitan sehingga membuat sufi,
seperti Hamzah Fansûrî merasa gelisah. Masyarakat yang terlalu sibuk dengan urusan
keduniannya ditegur Hamzah Fansûrî melalui karya yang indah berupa puisi dan
analogi-analogi sederhana dan mudah dipahami.
Berdasarkan analisis Ajaran Wujudiah Hamzah Fansûrî dan konteks
pengajarannya, dapat ditemukan bahwa ajaran tersebut menegaskan tentang kesatuan
wujûd yang hanya dinisbahkan kepada Haqq Ta’ala. Sementara kemajemukan alam
hanyalah seperti bayangan dalam cermin. Hubungan ketunggalan dan kemajemukan
Hamzah Fansûrî menggunakan analogi-analogi, seperti tanah dan perabotan, kayu
dan buah catur, matahari dan cahayanya, dan analogi-analogi lainnya yang mudah
516 Abdul Hadi WM, Tasawuf yang Tertindas…, 53. 517 Fansûrî, “Syarâb Al-Asyiqîn,”…, 287.
129
dipahami masyarakat. Hal ini berbeda dengan sufi dan filosof lain yang sebagian
menggunakan sistem yang rumit dalam menjelaskan ajarannya.
Dalam prinsip ajarannya, Hamzah Fansûrî menjelaskan bahwa dari dalam
napas al-Rahman sebagai kemajemukan bersumber. Segala kemajemukan itu berada
dalam ilmu Tuhan. Segala kemajemukan itu adalah wujûd wahmî, yakni pada
pandangan dia wujûd, namun pada hakikatnya wahmî. Pemahaman demikian adalah
berasal dari ilmu hakikat. Ilmu tersebut didapatkan dengan syarat tidak
menggantungkan diri pada dunia dan menempuh jalan suluk.
Dalam mengenal Allah, manusia dituntut untuk mengenal tujuh Sifat utama,
yakni Sifat pertama adalah Hayy, Sifat kedua adalah 'Ilmû, Sifat ketiga adalah Irâdat,
Sifat keempat adalah Qudrat, Sifat kelima adalah Kâlâm, Sifat keenam adalah Sâmî',
dan Sifat ketujuh adalah Basyar. Sementara penjelasan kejadian alam atau hubungan
antara ketunggalan dan kemajemukan dijelaskan melalui sistem ta’ayyûn. Ta’ayyûn
pertama adalah Ahadiyah, ta’ayyûn kedua adalah wahdah, ta’ayyûn ketiga adalah
wahidiyah, ta’ayyûn keempat adalah ‘alam arwah, ta’ayyûn kelima adalah ‘alâm
mitsal, ta’ayyûn keenam adalah ‘alâm ajsâm, dan ta’ayyûn ketujuh adalah ‘alam
insân.
Kondisi masyarakat Melayu yang maju di bidang ekonomi dan keduniaan
lainnya diingatkan Hamzah Fansûrî supaya dapat diseimbangkan dengan penyiapan
bekal untuk kehidupan kekal. Hamzah Fansûrî mengingatkan manusia itu seperti
seorang dagang, yakni datang sejenak ke suatu tempat dan akan kembali selama-
lamanya. Karena itu, manusia harus mempersiapkan bekal amal ibadah supaya dapat
selamat di akhirat kelak. Dalam menjelaskan hakikat kedirian insan, analogi anak
dagang itu sangat mudah dipahami. Ajaran-ajaran Hamzah Fansûrî memang mudah
dipahami dengan menggunakan analogi yang sesuai dengan konteks masyarakatnya.
Sufi, seperti Ibn 'Arabî yang hidup dalam periode masyarakat kosmopolitan di
Timur Tengah mendayagunakan hampir semua khazanah ilmu pengetahuan untuk
mengomunikasikan ajarannya. Sebab itulah, al-Futûhât hanya dapat dipahami
dengan baik bila menguasai berbagai perspektif keilmuan. Ibn ‘Arabî
mendayagunakan ilmu matematika, astronomi, kimia, dan tentunya filsafat untuk
mengomunikasikan ajarannya. Bahkan, analogi-analogi sederhana juga digunakan
Ibn ‘Arabî. Sebab itulah, bila belum menguasai antardisiplin keilmuan, al-Futûhât
sangat sulit dipahami518. Sementara Hamzah Fansûrî adalah sufi yang fokus
komunikasi ajarannya adalah dengan menggunakan analogi. Tentunya Hamzah
Fansûrî menggunakan objek analogi yang dekat dengan masyarakatnya. Meskipun
demikian, Hamzah Fansûrî juga menggunakan analogi-analogi yang telah digunakan
sufi-sufi sebelumnya selama objek-objek analogi itu relevan untuk masyarakat
Melayu. Misalnya, Hamzah Fansûrî menggunakan analogi besi dan api yang
sebelumnya telah digunakan Jalal al-Dîn Rûmî dan menggunakan analogi laut dan
ombak yang sebelumnya telah digunakan Ibn ‘Arabî519. Tentunya analogi-analogi
518 Chittick, The Self-Disclosure of God: Principles of Ibn Al-’Arabi’s Cosmology…,
x. 519 Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri…, 137–138. Sebenarnya sangat
banyak analogi yang berasal dari sufi sebelumnya yang dianggap relevan dan menjadi sarana
analogi yang mudah dipahami pembacanya di Indonesia. Tetapi tidak sedikit juga analogi baru
130
lain yang digunakan Hamzah Fansûrî adalah yang lebih dekat dengan masyarakatnya
sehingga menjadi lebih mudah dipahami.
Hamzah Fansûrî menyerap tradisi Wujudiah sebelumnya dari berbagai tokoh
sufi dan memformulasikannya dalam skema yang unik untuk disampaikan kepada
masyarakat Melayu. Dalam hal ini, tentunya Hamzah Fansûrî harus mampu
menyederhanakan Wujudiah yang sangat rumit dari para sufi sebelumnya agar dapat
dipahami masyarakat Melayu. Sebaliknya, sufi dan filosof lain, seperti Mullâ Sadrâ
melakukan sintesis atas pemikiran sebelumnya sehingga membuat ajarannya harus
sangat luas pembahasannya. Masyarakat Melayu membutuhkan pola sederhana
dalam pengajaran Wujudiah. Sementara pada masa itu, masyarakat Persia
membutuhkan sintesis atas pemikiran-pemikiran sebelumnya.
Hamzah Fansûrî dengan kejeniusannya memformulasikan Wujudiah yang
sangat rumit menjadi ungkapan-ungkapan simbolis dalam puisi-puisinya. Sementara
penjelasan yang lebih dekskriptif terdapat dalam prosa-prosanya, khususnya Asrâr
yang secara deskriptif filosofis menggunakan banyak analogi yang mudah dipahami
masyarakat Melayu untuk menjelaskan ajaran Wujudiah.
Sebagian masyarakat dan sarjana menganggap ajaran Hamzah Fansûrî sangat
sulit dipahami sehingga menjadi enggan atau menggunakan persiapan yang rumit
untuk menelaah ajaran-ajarannya, ternyata ajarannya itu sangat mudah dipahami.
Melakukan persiapan tertentu yang terlalu elitis, seperti teori yang besar dan
metodologi yang rumit, hanya membuat ajaran Hamzah Fansûrî menjadi makin
kabur. Padahal, ternyata ajarannya itu sangat sederhana. Analogi yang digunakan
sangat dekat dengan keseharian masyarakat pada zamannya.
Menganggap teks karya Hamzah Fansûrî sebagai misteri telah membuat makna
ajarannya terkonsumsi oleh sebagian kalangan saja. Terdapat juga kemungkinan
sebagian sarjana, terutama mereka yang sudah punya asumsi bahwa ajaran Hamzah
Fansûrî itu sesat, membuat dan menyebarkan kesan bahwa ajaran Hamzah Fansûrî itu
rumit dan sulit dipahami agar masyarakat enggan mempelajarinya. Padahal, idealnya
sebuah ajaran harus mampu dikomunikasikan dengan mudah bagi segenap lapisan
masyarakat.
Di antara empat analogi utama, yakni tanah dan perabotan, matahari dan
sinarnya, kayu dan buah catur, dan laut dan ombak, analogi tanah dan perabotan dapat
menjadi analogi terbaik karena objeknya dapat ditemukan dengan mudah dalam
kehidupan sehari-hari. Sangat banyak benda yang dibangun, didesain, dan dibuat dari
tanah. Setiap hari manusia tidak dapat menghindar dari objek-objek itu. Karena itu,
ketika sedikit saja menggunakan perenungan, kesadaran Ilahiah dapat muncul. Di
samping itu, analogi tanah analogi tanah sangat akurat karena banyak hal yang dapat
dibuat dengan mudah dari tanah. Banyak objek yang sebenarnya keseluruhannya dari
tanah, sementara jenis benda yang dapat dibuat darinya sangat banyak.
Cahaya adalah analogi yang sangat disukai ‘urafâ. Hal ini karena cahaya
sebagai sesuatu yang sangat terang sehingga tidak membutuhkan definisi padanya.
Bahkan, mendefinisikan cahaya malah mereduksi. Cahaya juga merupakan sesuatu
yang sangat dekat, menyeluruh, dan mengisi kehidupan manusia. Cahaya yang
yang dibuat Hamzah Fansûrî yang sesuai untuk masyarakat Kepulauan-Indonesia. Analogi
biji sebagai kanzân makfî atau perbendaharaan tersembunyi juga dari Ibn’Arabî.
131
terpancar dengan berbagai warna, beragam intensitas ketika menghantam prisma
adalah analogi yang sangat disukai dalam usaha menerangkan Bâsîth520.
Kayu dapat menjadi analogi yang sangat akurat karena alasan seperti tanah
juga. Analogi kayu sebenarnya tidak sesederhana yang dicontohkan Hamzah Fansûrî,
yakni biji-biji catur. Dari kayu dapat dibuat sangat banyak perabotan, sangat banyak
hiasan, dan sangat banyak perkakas. Di samping itu, tanah juga sangat penting
sebagai analogi karena sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Laut juga merupakan analogi yang sangat disukai ‘urafâ karena akurasi
analoginya. Laut yang sangat luas, seperti tidak berujung dan memiliki kedalaman
yang tidak terjangkau adalah sifat-sifat laut yang mirip dengan sifat-sifat Bâsîth.
Analogi tanah yang menghasilkan berbagai perabotan dibedakan dengan bumi yang
dijadikan analogi ‘Ilmû Bâsîth dan air hujan yang dianalogikan dengan Wujûd-Nya.
Bila tidak ada air hujan, tidak akan tumbuh pepohonan. Demikian wujûd makhlûqat
tidak akan pernah hadir tanpa pemberian wujûd dari Bâsîth521. Analogi cahaya dan
sinarnya digunakan untuk menggambarkan manifestasi Ilahi kepada beragam
makhluk. Seperti cahaya matahari yang menyinari dan memberikan sinar kepada
berbagai entitas, demikianlah Haqq Ta’ala memberikan wujud kepada sekalian alam.
Analogi kayu dan berbagai buah catur digunakan untuk menggambarkan
bahwa dari satu hakikat muncul berbagai nama, namun sejatinya hanya satu. Seperti
berbagai larik buah catur, raja, menteri, gajah, kuda, benteng, dan bidak, semuanya
sejatinya hanya satu wujûd\. Persis seperti berbagai entitas alam, sejatinya hanya satu
wujûd dalam ajaran Hamzah Fansûrî. Analogi laut dan ombak digunakan untuk
menjelaskan bahwa makhluk dan Haqq Ta’ala itu tiada berpisah. Persis seperti laut
dan ombak. Namanya berbeda, tetapi hakikatnya adalah laut. Sebagaimana alam
menjadi penanda bagi eksistensi Haqq Ta’ala, demikian juga ombak yang tampak
menunjukkan adanya hakikat laut.
Adapun analogi-analogi sekunder adalah analogi ontologi yang tidak secara
langsung bermaksud menjadikan objek-objek yang dianalogikan untuk menjelaskan
tentang Haqq Ta’âlâ. Analogi-analogi tersebut memang masih masih berkaitan
dengan penjelasan tentang Bâsîth, tetapi lebih bertujuan menjelaskan hubungan
Bâsîth dengan makhlûqat. Objek-objek analogi tersebut adalah buah, biji, cermin,
manusia, air, batu, dan besi.
Analogi buah yang bulat itu dibuat Hamzah Fansûrî untuk menganalogikan
Sifat Qadim. Sifat tersebut tidak memiliki batasan seperti buah. Tidak dapat
diidentifikasi batas-batasnya. Tidak berlaku baginya batas-batas, seperti permulaan,
kesudahan, tepian, bagian depan, bagian belakang, bagian, kiri, bagian kanan, bagian
bawah, dan bagian atas. Qadim itu adalah sifat kekal yang tidak memiliki
perumpamaan dan tidak berlaku baginya pengakhiran522. Apabila satu bagian berlaku
bagi Qadim, bagian lawannya akan berlaku pula. Misalnya, apabila memiliki
permulaan, pasti memiliki akhiran. Apabila berlaku bagian depan, pasti berlaku
bagian belakang. Apabila berlaku bagian kiri, pasti terdapat bagian kanannya.
520 Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri…, 242. 521 Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri…, 268. 522 Udi Mufrodi, “Alam Semesta Dan Keabsolutan Tuhan,” ALQALAM 22, no. 3
(December 30, 2005): 335, http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/1365.
132
Apabila berlaku bagian bawah, pasti terdapat bagian atas. Apabila memiliki
permulaan, pasti memiliki akhiran. Ketika semua batasan ini berlaku, sifat Qadim itu
tentunya tidak dapat diidentifikasi dan tidak dapat dilimitasi karena tidak berlaku
baginya kategori, baik substansi maupun aksiden523.
Analogi biji digunakan Hamzah Fansûrî dalam menjelaskan kanzân
makhfiyyân, yakni perbendaharaan tersembunyi. Pada hadis qudsi, Al-Haqq juga
menganalogikan Diri-Nya sebagai “perbendaharaan tersembunyi”, yaitu kanzan
makfiyyan. Adapun bunyi hadis qudsi dimaksud adalah, “Kuntû kanzân makhfiyyân
fa ahbabtu ‘an ‘urafâ”. Analogi bagi “perbendaharaan tersembunyi” oleh Hamzah
Fansûrî adalah “biji”. Pada biji telah terkandung segala entitas pohon, seperti
akarnya, batangnya, cabangnya, dahannya, daunnya, rantingnya, dan buahnya.
Analogi ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam pandangan ‘urafâ, segala
wujûd selain Al-Haqq telah mengada bersama-Nya sehingga wujûd selain Al-Haqq
bukanlah wujûd baharu. Analogi ini dipakai untuk menyanggah argumentasi
mutakallimîn yang menyatakan bahwa makhlûqat berasal dari ketiadaan. Biji yang
dimaksud untuk menyebutkannya sebagai benih yang dapat menumbuhkan pohonnya
kembali. Biji adalah bagian dari buah yang umumnya di dalam dan menjadi inti buah.
Dari biji dapat disemai menjadi buah karena pada biji tersebut telah terkandung
totalitas buah. Penunjukan biji sebagai analogi menjadi akurat karena mustahil
membayangkan keterpisahan suatu tumbuhan dari sumbernya, yakni biji. Analogi ini
diakui Hamzah Fansûrî diambilnya dari Ibn ‘Arabî524.
Hamzah Fansûrî menganjurkan manusia untuk menghilangkan kedirian karena
kedirian manusia, serta segala yang disandang manusia itu tidak nyata, segalanya
hanya seperti bayang-bayang. Pengakuan atas eksistensi kedirian adalah hijab dalam
rangka menenggelamkan diri dalam samudra Ilahi.
Manusia dalam ajaran Hamzah Fansûrî menjadi analogi untuk
menggambarkan hubungan Dzat dengan sifat-sifatnya. Misalnya, Hamzah Fansûrî
menggunakan analogi seseorang. Misalnya, Muhammad sebagai analogi Dzat,
sebagai Huwa yang tidak dikenal. Pengenalan Dzat hanya melalui sifat-sifatnya.
Ketika Muhammad memiliki pengetahuan, dia disebut ‘alim. Ketika Muhammad
menulis, disebut katib. Ketika Muhammad berdagang disebut saudagar525.
Analogi lain tentang manusia adalah seorang raja. Analogi ini digunakan untuk
menggambarkan bagaimana ‘Ilmû Bâsîth teraktualisasi sebagai alam semesta. Bila
mengatakan Bâsîth sebagai ‘Alim, namun tiadanya alam semesta, itu seperti seorang
raja yang tidak memiliki prajurit atau seorang yang memiliki ilmu pengetahuan, tetapi
tidak mengamalkannya526.
Utus dianalogikan dengan keteraturan ciptaan. Suatu pekerjaan apabila
dilakukan oleh ahlinya, akan lahir karya yang teratur, rapi, dan kukuh sebagaimana
eksistensi alam semesta. Utus juga dalam kajian tasawuf falsafi dapat menjadi analogi
ilmu Tuhan dan aktualisasi ilmu-Nya. Segala ciptaan sebenarnya sudah ada dalam
523 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 241. 524 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 253. 525 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 240 526 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn”…, 253–255.
133
ilmu Tuhan sebelum menjelma. Sama seperti sebuah gedung sudah ada dalam
inteleksi imajinasi seorang utus sebelum rumah itu diaktualisasikan dengan dibuat527.
Di samping menjadikan manusia sebagai analogi, jasad manusia dianalogikan
dengan perahu. Manusia harus selalu mengingat, tubuhnya seperti perahu. Segala
bekal perlu dipersiapkan. Manusia harus selalu ingat bahwa bagi dirinya yang seperti
perahu, daratan hanya persinggahan sementara. Hakikatnya akan segera
berlabuh528. Pada momen persinggahan, sebagaimana kehidupan di dunia, harus
mempersiapkan bekal untuk kembali berlabuh. Perjalanan jiwa manusia masih sangat
panjang.
“Anak mu'allim tahu akan jalan
Da'im berlayar di laut nyaman
Markab-mu tiada berpapan
Oleh itu tiada berlawan”529
“Ya’ni di atas segala ‘alam BekasNya lalu; seperti air sungai lalu tiada
berkeputusan [dan] tiada berkesudahan.”530
Pada bagian ini, Hamzah Fansûrî menggunakan sungai sebagai analogi bagi
eksistensi alam semesta yang merupakan hakikat kehadiran Wujûd Bâsîth secara terus
menerus. Aliran sungai yang mengalir terus-menerus adalah analogi tentang
bagaimana eksistensi makhluk terjadi secara terus-menerus. Al-Qur’an (55: 29)
menyebutkan bahwa Allah senantiasa dalam kesibukan.
يسـله من فى السموت والرض كل يوم هو في شأن
Artinya:
“Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap waktu Dia
dalam kesibukan.”
Munculnya keberagaman pada makhlûqat yang sejatinya berasal dari satu
wujûd dianalogikan dengan hadirnya berbagai jenis, bentuk, warna, dan rasa buah-
buahan. Meskipun beragam, semua itu berasal dari ‘Ilmû dan Wujûd Haqq Ta’âlâ.
Persis seperti munculnya beragam jenis, rasa, dan warna buah-buahan yang berasal
dari air. Sumbernya itu satu, tetapi memunculkan keberagaman buah-buahan.
Demikian dianalogikan wujûd, satu asalnya, tetapi menjadi beragam. Analogi air
muncul dari penakwilan atas Al-Qur’an (13: 4).
غير صنوان يسقى نخيل صنوان و زرع و ن اعناب و جنهت م تجورت و احد وفى الرض قطع م بماء و
ل بعضها على بعض نفض يت ل قوم يعقلون فىو الكل ان في ذلك ل
Artinya:
527 Willam C. Chittick, The Self-Disclosure of God: Principles of Ibn Al-’Arabi’s
Cosmology (New York: State University of New York Press, 1997), 187. 528 Abdul Hadi WM., Tasawuf yang Tertindas…, 168. 529 Abdul Hadi WM., Tasawuf yang Tertindas…, 365. 530 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn”…, 265.
134
“Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun
anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak
bercabang; disirami dengan air yang sama, tetapi Kami lebihkan tanaman yang
satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti.”
Air dianalogikan sebagai dari satu wujûd memunculkan beragam fenomena,
menjadi siang dan malam, menjadi langit dan bumi, menjadi ‘arsy dan kursî, menjadi
surga dan neraka, menjadi Islam dan kafir, dan menjadi baik dan jahat, semuanya
berasal dari Bâsîth. Air sebagai entitas dasar juga dianalogikan sebagai Bâsîth sebagai
kanzân makfî (perbendaharaan tersembunyi). Sementara buih yang beragam corak,
beragam warna dan berbagai bentuk sejatinya adalah aktualitas air. Sebagaimana
keberagaman alam semesta merupakan aktualitas dari perbendaharaan tersembunyi.
Hubungan air dan buih juga menjadi analogi dalam menjelaskan hubungan
pesuluk dengan Bâsîth. Pesuluk dianalogikan dengan buih yang sejatinya kembali
(wasil) kepada air yang dianalogikan sebagai Bâsîth. Namun akhirnya, Hamzah
Fansûrî menegaskan bahwa wasil itu pun sebenarnya hanyalah kiasan, bukan dengan
makna sebenarnya. Karena itu, hanya merupakan cara untuk dapat mengenal Allah.
Karena itu, konsistensi kepada syariat harus senantiasa teguh531.
Batu adalah analogi ketiadaan daya manusia. Seperti sebuah batu yang sama
sekali tidak dapat berkehendak atas dirinya sendiri, demikian juga manusia dan segala
makhlûqat. Semua tunduk pada kendali Bâsîth. Batu juga menjadi analogi untuk
menjelaskan kondisi fânâ. Hamzah Fansûrî mengatakan bahwa fânâ sejati adalah
ketika emas dan batu sekaligus tidak dapat diidentifikasi. Karena bila masih mampu
mengidentifikasi emas, tentunya masih mengakui eksistensi ketuhanan (Ya’ni tamthil
emas [itu iaitu] Tuhan…). Bila masih mengakui eksistensi Tuhan, meniscayakan
eksistensi makhlûqat sehingga masih terkandung dualitas. Dan kondisi dualitas
belum merupakan perjalanan spiritual yang tinggi532. Bahkan, dalam kondisi
pengalaman spiritual yang tinggi, segenap Nama dan Sifat yang dipredikasi kepada
Bâsîth harus dilenyapkan karena segala sifat-sifat itu ternyata adalah hijab.
Dinding Dhat itu Sifat
Dinding sifat itu asma’
Dinding asma’ itu af’al
Dinding af’al itu athar533
“Batu” dianalogikan Hamzah Fansûrî sebagai maqâm bagi orang telah
menjadi faqir secara mutlak, yakni telah mencapai maqâm (derajat) makrifat. Batu
tidak dapat bergerak, kecuali ada daya dari luarnya yang menggerakkan. Demikian
pula orang pesuluk yang telah mencapai maqam ma’rifat, ia tidak memiliki apa pun,
kecuali segalanya adalah kehadiran Bâsîth. Segala diam dan geraknya adalah total
kehadiran Al-Haqq.
531 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn”…, 294–295. 532 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn”…, 289. 533 Al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansûrî,…, 290.
135
Besi dan pedang adalah analogi kesatuan subjek yang mengetahui (‘alim) dan
objek yang diketahui (ma’lûm) yang merupakan haqîqit muhammadî, yakni nûr
Muhammad. Hamzah Fansûrî menganalogikan hal-hal yang dimaknai manusia
sebagai keburukan seperti sepotong besi. Besi itu sejatinya tidak memiliki daya. Besi
hanya memiliki potensi untuk diubah menjadi keris. Ketika seseorang melakukan
pembunuhan menggunakan keris tersebut, daya keris itu memenuhi hukum yang
ditetapkan kepadanya534. Hukum potensi kepada keris itulah yang digambarkan
sebagai Sifat Ilahi sehingga tidak ada peluang untuk mengatakan bahwa keburukan
itu datang dari Allah dan Sifat-sifat-Nya. Gagang pancing digunakan untuk analogi
bagaimana sebenarnya segala yang datang dari Bâsîth adalah kebaikan. Seperti
gagang pancing meskipun dipandang bengkok535, tetapi itulah kesempurnaan
aktualitasnya. Segala realitas baik dan buruk hanya dalam penilaian mental
manusia536.
Sebenarnya terdapat analogi yang dibuat Hamzah Fansûrî untuk menjelaskan
Bâsîth, seperti analogi susu dan minyak sapi. Bahwasanya keseluruhan minyak sapi
sebenarnya adalah susu. Perbedaan hanya terjadi pada penamaan, pada keseluruhan
minyak sapi sebenarnya adalah susu. Demikian sebenarnya Bâsîth yang hadir pada
realitas alam yang sebenarnya adalah kehadiran Bâsîth secara keseluruhan.
Analogi lainnya yang sangat akurat yang digunakan Hamzah Fansûrî untuk
menjelaskan Bâsîth adalah kain dengan kapas537. Kain merupakan kehadiran total
kapas. Yang tampak terlihat adalah kain, namun keseluruhan kain itu sebenarnya
adalah kapas. Manusia melihat fenomena berbagai ragam, diberi berbagai nama.
Namun, hakikatnya adalah wujûd yang satu538.
Yogya kau pandang kain dan kapas
Keduanya wahid asmanya lain
Wahidkan hendak zahir dan batin
Itulah ilmu kesudahan main539
534 Al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansûrî,… 261–262. 535 Al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansûrî,…, 290. 536 Teuku Safir Iskandar Wijaya, Falsafah Kalam, (Lhokseumawe: Nadiya Foundation,
2003), 72. 537 Drewes dan Brakel, The Poems of Ḥamzah Fansûrî…, 88. 538 Toshihiko Izutsu, Sufism and Taoism: A Comparative Study of Key Philosophical
Concepts…, 160. 539 Abdul Hadi WM., Hamzah Fansûrî: Risalah Tasawuf dan Puisi-Puisinya,
(Bandung: Mizan, 1995), 108.
136
BAB IV
ANALISIS FILSAFAT MULLÂ SADRÂ
Mullâ Sadrâ adalah pemikir yang hadir dalam masa kemunduran keilmuan di
dunia Islam secara keseluruhan. Namun, masa itu merupakan masa perkembangan
keilmuan di Persia. Pada masa tersebut, para pemikir di sana sedang berusaha
menyusun karya yang menyintesiskan berbagai aliran dalam pemikiran Islam.
Gurunya Mullâ Sadrâ, Mîr Dâmâd telah melakukan usaha tersebut. Semangat itu
diwarisi Mullâ Sadrâ dengan menghasilkan karya yang dianggap merupakan sebuah
sintesis dalam pemikiran Islam. Karena merupakan sebuah karya yang dibangun
berdasarkan analisis atas berbagai tema dalam pemikiran Islam sebelumnya, menjadi
sulit mempelajari filsafat Mullâ Sadrâ tanpa lebih dahulu mengakrabkan diri dengan
karya-karya filsafat sebelumnya, khususnya karya yang dikembangkan oleh para
filosof muslim, seperti Ibn Sînâ dan Syihab al-Dîn al-Suhrawardî.
Dalam mengembangkan sistem filsafatnya, Mullâ Sadrâ merespons berbagai
aliran pemikiran, tidak hanya dalam dunia Islam, tetapi juga dari berbagai khazanah
ilmu pengetahuan sebelum Islam, seperti filsafat Persia dan filsafat Yunani. Filsafaf
Mullâ Sadrâ dikemukakan dalam beberapa karyanya, seperti Asfar dan al-Masya’ir.
Karya tersebut pertama berisi deskripsi panjang Mullâ Sadrâ dalam membangun
argumentasi-argumentasi penting dalam konsep-konsep ajarannya. Sementara karya
tersebut kedua merupakan semacam kesimpulan-kesimpulan Mullâ Sadrâ dari hasil
deskripsi argumentasi teori-teorinya.
Secara keseluruhan, pemikiran Mullâ Sadrâ niscaya berkaitan dengan
pemikiran filsafat, tasawuf, dan teologi sebelumnya. Konsep-konsep penting dalam
pemikiran Mullâ Sadrâ, seperti gradasi wujûd (tâskîk al-wujûd), gerak substansi (al-
harakah al-jawhayiah), dan kesatuan subjek dan objek (ittihad aqil wa ma’qûl),
adalah konsep-konsep yang hanya dapat dipahami dengan mudah apabila telah
memahami konteks respons Mullâ Sadrâ atas pemikiran-pemikiran sebelumnya.
Sebab itulah, analisis pemikiran Mullâ Sadrâ hanya dapat dipahami dengan mudah
dengan didahului deskripsi atas pemikiran filsafat sebelumnya.Bagian ini terbagi
menjadi empat pembahasan, yakni dimulai dengan membahas kehidupan dan karya
Mullâ Sadrâ secara sepintas. Kemudian, membahas tentang gagasan utama filsafat
Mullâ Sadrâ yang membahas secara umum gagasan Mullâ Sadrâ yang coba dibagi
menjadi bagian pemikiran ontologi dan epistemologi. Bagian selanjutnya adalah
analisis tetang konsep penting dalam filsafat Mullâ Sadrâ dan mencoba berfokus
pada konsep-konsep penting, seperti kemendasaran wujûd (ashalat al-wujûd), gradasi
wujûd (tâskîk al-wujûd), kefakiran akibat dalam kausalitas (illiyah), hakikat
sederhana (basith al-haqîqah), gerak substansi (al-harakah al-jawhayiah), dan
kesatuan subjek dan objek (ittihad aqil wa ma’qûl). Bagian terakhir merupakan
pandangan penyimpulan dari gagasan-gagasan Mullâ Sadrâ.
A. Kehidupan dan Karya Mullâ Sadrâ
Diperkirakan Mullâ Sadrâ hidup sekitar 1571 sampai dengan 1640 M. Tidak
ada yang tahu pasti tanggal kelahirannya. Dia lahir di Syirâz negeri Persia. Di sana,
pada masa itu berkembang dengan baik tradisi ilmu pengetahuan. Karena dilahirkan
137
dari keluarga petinggi negara, Mullâ Sadrâ menjadi mudah menuntut ilmu dan
mengakses buku-buku yang dibutuhkan. Mullâ Sadrâ tidak tertarik dengan jabatan
negara sebagaimana orang tuanya. Dia hanya fokus untuk terus-menerus menuntut
ilmu dan memperdalam pengetahuannya di berbagai bidang keilmuan540.
Mullâ Sadrâ berguru pada Bahâ al-Dîn al-‘Amilî, Mîr Dâmâd, dan Mîr ‘Abd
al-Qâshim Findirîskî. Setelah mendalami ilmu-ilmu filsafat, kalam, dan agama-
agama di Isfahan, Mullâ Sadrâ hijrah ke Kahak untuk melatih rohani selama lima
belas tahun hingga mengaku telah memperoleh penyingkapan spiritual. Setelah
menyendiri itu, Mullâ Sadrâ dituduh sesat oleh para mutakallimîn dan ahli fikih. Dia
menuduh balik para mutakallimîn dengan mengatakan mereka tergelincir dari
pemahaman pemikiran yang benar (ilmu logika) dan terganggu jiwanya541.
Pada masa kembali di kota kelahirannya, Mullâ Sadrâ memimpin sebuah
madrasah. Dia menulis magnum opus-nya al-Hikmah al-Muta'alliyah fî al-Asfar
'Aqliyah al-Arba'aah yang biasanya disingkat dengan Asfar. Mullâ Sadrâ tinggal di
kota kelahirannya selama tiga puluh tahun dan meninggal di Basrah pada perjalanan
pulang dari ibadah hajinya yang ketujuh kali dengan berjalan kaki. Ahmad dan
Muhammad adalah anak Mullâ Sadrâ yang nantinya meneruskan ajaran ayahnya
beserta 'Abd al-Râzaq Lahijî yang merupakan menantunya542.
Mîr Dâmâd adalah salah satu guru terpenting Mullâ Sadrâ. Gurunya ini
menguasai al-Hikmah al-Masyâ'iyyah, al-Hikmah al-Isyrâqiyyah, dan tasawuf
filosofis. Mîr Dâmâd mencoba menyintesiskan tiga ajaran tersebut meski nantinya
muridnya, Mullâ Sadrâ melanjutkan usahanya. Mîr Dâmâd juga seorang seniman
yang mengarang puisi bagus. Guru Mullâ Sadrâ lainnya, Mîr ‘Abd al-Qâshim
Findirîskî menguasai Peripatetik dan agama-agama di luar Islam, khususnya Hindu.
Guru lainnya Bahâ al-Dîn al-‘Amilî berasal dari Lebanon, tetapi kelak menjadi
sastrawan Persia543. Ternyata pada periode Mullâ Sadrâ, para pemikirnya suka
melakukan sintesis antaraliran pemikiran. Sebelumnya, Nasr al-Dîn Thûsî telah
berusaha menyintesiskan teologi dan filsafat seperti yang dilakukan pada masa
kontemporer oleh Jawadî Amulî dalam menyintesiskan tasawuf dan teologi.
Semua karya Mullâ Sadrâ ditulis dalam bahasa Arab. Jumlahnya sekitar empat
puluh judul544. Karya penting Mullâ Sadrâ adalah Asfar. Editan terbarunya dilakukan
oleh Sayyîd Hussâin Thabâttabâ'i pada 1975 sebanyak sembilan jilid. Karya Iksâr
'Arifîn yang membahas tentang kajian mengenai ilmu telah diterjemahkan ke dalam
bahasa Jepang oleh Sijiru Kamada telah diterbitan oleh di Universitas Tokyo pada
1983. Al-Mazâhîr al-Ilâhîyah’ berbicara tentang ketuhanan dan hari kiamat. Al-
Mabda' wa al-Ma'ad mengulas metafisika, kosmologi, dan eskatologi. Karya
540 James Winston Morris, dalam Mulla Sadrâ, Kearifan Puncak, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004), 18 541 Hasan Bakti Nasution, “Hikmah Muta’alliyah: Analisa Terhadap Proses Sintesa
Filosofis Mulla Sadra” (IAIN Jakarta, 2001), 29. 542 Kerwanto, “Pemikiran Filosofis Sadra Dalam Tafsir Al-Qur’an Al-Karim : Surah
Al-’A‘la,” 23. 543 Nasr, “Existence (Wujūd) and Quiddity (Māhiyyah) in Islamic Philosophy,”408. 544 Nasution, “Hikmah Muta’alliyah: Analisa Terhadap Proses Sintesa Filosofis Mulla
Sadra,” 37.
138
berjudul al-Masyâ'ir membahas tentang wujûd dan dapat dikatakan sebagai
ungkapan-ungkapan penyimpulan tentang pandangan ontologinya dalam Asfar. Al-
Syawahid al-Rubûbîyah fîManhaj al-Sulûkîyyah membahas tentang tawawuf
filosofis. Al-Hikmah al-'Arsiyyah’ mengulas tentang perjalanan manusia setelah
kematian. Mullâ Sadrâ juga menulis empat judul tentang tafsir. Dia juga menulis
beberapa judul tentang komentarnya atas pemikiran Ibn Sînâ dan Syîhab al-Dîn al-
Suhrawardî. Selain melakukan kritik, Mullâ Sadrâ telah melakukan banyak
penyerapan gagasan-gagasan penting dalam khazanah intelektual sebelumnya dalam
membentuk mazhab pemikirannya. Di antara gagasan yang sangat banyak diserap
Mullâ Sadrâ adalah dari Wujudiah Ibn ‘Arabi, al-Hikmah al-Masyâ'iyyah Syihab al-
Dîn al-Suhrawardî, dan al-Hikmah al-Masyâ'iyyah Ibn Sînâ.
Pandangan Mullâ Sadrâ tentang kemendasaran dan kesatuan wujûd tidak hanya
dipengaruhi oleh Ibn Sînâ dan Syihab al-Dîn al-Suhrawardî, namun juga pengajar
Wujudiah, khususnya Ibn ‘Arabî. Dia satu-satunya pemikir yang hampir tidak
mendapatkan kritik dari Mullâ Sadrâ. Bahkan, Ibn ‘Arabî adalah salah satu pemikir
yang paling memengaruhi pemikiran Mullâ Sadrâ545. Fazlur Rahman mengatakan, di
antara gagasan Ibn ‘Arabî yang sangat memengaruhi Mullâ Sadrâ adalah tentang
ketiadaan realitas mâhiyâh yang dengan itu Mullâ Sadrâ membangun pandangan
kesatuan wujûd. Namun, Mullâ Sadrâ tetap mempertahankan tâskîk al-wujûd sebagai
konsistensi pada gerak substansi yang dia bangun sehingga dianggap sebagai sebuah
terobosan dalam filsafat546.
Pengaruh lainnya dari Ibn ‘Arabî kepada Mullâ Sadrâ adalah keniscayaan
alam imajinal. Dalam pandangan sufi, alam imajinal itu, bahkan lebih riil daripada
alam materi. Maka dari itu, mimpi para nabi misalnya, diterima sebagai suatu yang
riil547. Mullâ Sadrâ dalam hal ini membangun sistem fakultas-fakultas jiwa, seperti
daya indrawi, imajinasi, dan inteleksi. Semua fakultas itu sejatinya adalah kehadiran
jiwa. Mullâ Sadrâ tidak dapat dilepaskan dari prinsip ajaran Wujudiah. Terkait
dengan kajian keilmuan, ajaran ini adalah analisis sejauh mana ilmu berkaitan dengan
karakter dasarnya, kesahihan ilmu yang berbeda dengan ilmu intelektual, dan dan
studi mengenai dasar-dasar konsep sehingga ajaran yang dalam tradisi Persia
diistilahkan dengan ‘irfan ini berarti suatu kajian tentang pengetahuan terdalam yang
dimiliki manusia. Istilah ini disebut dengan 'irfan yang berarti pengenalan terdalam.
Ilmu ini hanya didapatkan orang-orang tertentu. Ilmu ini diperoleh melalui qalb, ruh,
dan sirr. Salah satu pendiri aliran ini adalah Ibn 'Arabî.
Wujudiah yang dikembangkan Ibn 'Arabî menegaskan yang nyata hanya
hanyalah Haqq Ta’ala. Dia adalah Awal dan Akhir, Zahir dan Batin. Selain Dia
hanyalah bayangan seperti pantulan cermin. Dia bertajali melalui beberapa tahap
yang disebut martabat. Martabat pertama adalah Ahadiyyah yang merupakan
kemurnian tak terjangkau karena tanpa nama dan sifat. Martabat kedua adalah
Wahidiyyah, yaitu kondisi zat murni baru mengandung potensi untuk mengandung
545 Muthahhari, Filsafat Hikmah: Pengantar Pemikiran Shadra, 120–121. 546 Rahman, The Philosophy of Mulla Sadra (Sadr Al-Din Al-Shirazi), (New York:
State University of New York Press ,1975), 34–35. 547 Izutsu, Sufism and Taoism: A Comparative Study of Key Philosophical Concepts,
7.
139
nama. Ketiga adalah tajallî syuhudî yang telah memiliki nama dan sifat. Sistem
penjelasan hubungan Haqq Ta’ala, sebagai Pencipta yang berelasi dengan makhluk.
Dalam menjelaskan sistem ini, antara lain, menggunakan analogi angka. Hal yang
nyata hanya angka satu, sementara angka-angka seterusnya adalah bergantung pada
satu. Juga dijelaskan melalui analogi makanan spiritual, yaitu Haqq mengisi makhluk
dan makhluk mengisi Khalik. Analogi lainnya adalah Pencipta sebagai tubuh dan
makhluk sebagai anggota tubuh yang bukan apa-apa, kecuali direlasikan dengan
tubuh. Ajaran tersebut menginspirasi Mullâ Sadrâ dalam merumuskan sistem
Kesatuan yang mengalir dalam keberagaman dan keberagaman kembali kepada
kesatuan548.
Ibn 'Arabî membagi ilmu kepada ilmu ahwal, yaitu persepsi indrawi, ilmu
ta'alluq, yakni ilmu ma'qulat atau ilmu penalaran, dan ilmu zawqî, yaitu ilmu
pengenalan langsung. Ini disebut ma'rifat. Pengetahuan ini bersifat bawaan atau
berada pada posisi pasif, tidak bisa diukur secara rasional, bisa diusahakan, tetapi
hasilnya adalah bagi yang terpilih. Pengetahuan ini adalah pengetahuan Ilahi. Mullâ
Sadrâ menerima pandangan demikian dalam sistem kehadiran daya jiwa dalam
bentuk indrawi, inteleksi, imajinasi, dan intuisi (hudhûrî)549.
Dalam pandangan Syihab al-Dîn al-Suhrawardî, ilmu terbagi atas kosmologi,
astronomi metafisika, dan logika. Sistem perolehan ilmu menurutnya adalah idhraki,
yakni persepsi indrawi; hushûlû, yaitu penalaran rasional; dan hudhûrî, yakni
penyingkapan spiritual. Syihab al-Dîn al-Suhrawardî merumuskan sistem
pengetahuan itu dalam ceritanya bermimpi berjumpa Aristoteles dan menanyakan,
“Apa, bagaimana memperoleh, apa muatan, dan bagaimana menilai ilmu.”
Aristoteles menjawab, "Kembalilah pada dirimu". Sehingga akhirnya, Syihab al-Dîn
al-Suhrawardî meyakini bahwa ilmu yang nyata itu adalah pengenalan diri550.
Semangat itu menginspirasi Mullâ Sadrâ untuk menjadikan kasyaf hudhûrî sebagai
prasyarat perolehan pengetahuan551.
Wujudiah atau tasawuf filosofis adalah ajaran yang menyatakan wujûd itu
hanya satu. Banyak kalangan mencoba mengaitkan Wujudiah dengan Mullâ Sadrâ.
Alasan mereka adalah Mullâ Sadrâ mengajarkan wujûd adalah satu, namun
bergradasi (taskîk). Sistem taskîk diinspirasikan oleh Syihab al-Dîn al-Suhrawardî
dari ajaran manifestasi cahaya. Dalam ajaran taskîk al-wujûd, perbedaan dalam satu
wujûd adalah pada kedahuluan-kebelakangan dan kesempurnaan-
kekurangsempurnaan552.Tokoh penting yang dipengaruhi Mullâ Sadrâ adalah Mullâ
548 Cipta Bakti Gama, Filsafat Jiwa: Dialektika Filsafat Islam, dan Filsafat Barat
Kontemporer, 113. 549 Kholid Al-Walid, Tasawuf Mulla Shadra: Konsep Ittihad Al-’Aqil Wa Al-Ma’qul
Dalam Epistemologi Filsafat Dan Makrifat Ilahiyyah (Bandung: MPress, 2005), 127. 550 Hasan Bakti Nasution, “Hikmah Muta’alliyah: Analisa Terhadap Proses Sintesa
Filosofis Mullâ Sadrâ” (IAIN Jakarta, 2001), 96–97. 551 Ismail Fahmi Arrauf Nasution, “Mencerna Akar Filsafat Dalam Islam,” Ulumuna
17, no. 1 (2013): 1-18. 552 Mulla Sadra, Al-Hikmah Muta‟aliyyah fî al-Ashfâr al’Aqliyyah Al-Arba’ah, Vol. 1
(Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-’Arabî, 2002), 92.
140
Hâdî Sabzawarî, Mullâ Alî Nûrî, Mulla Alî Mudarris Zunûzî, dan Muhammad
Hidâjî553
Di Barat, ajaran Mullâ Sadrâ diperkenalkan oleh Henry Corbin, Max Horten,
Fazlur Rahman, dan Seyyed Hossein Nasr. Di India, ajaran Mullâ Sadrâ dibawa oleh
Muhammad Salîh Kassânî554. Di Indonesia, pemikiran filsafat pasca Abû Hamid al-
Ghazâlî baru diperkenalkan penerbit Mizan dan penerbit Pustaka di Bandung dengan
mengulas pemikiran-pemikiran intelektual Persia, seperti Murtadha Muthahari dan
Ali Syariati555. Nurcholish Madjid melihat di antara problem yang dihadapi
masyarakat dalam dunia intelektual adalah keengganan mengakses literatur
pemikiran Persia. Padahal di sana, pasca Abû Hamid al-Ghazâlî, pemikiran filsafat
makin maju556. Oleh para pendukung dan pengkaji pemikirannya, Mullâ Sadrâ
dianggap telah mampu menyintesis berbagai aliran filsafat sebelumnya, seperti al-
Hikmah al-Isyrâqîyah (Illuminasionisme) dan al-Hikmah al-Masya'iyyah
(Peripatetik); kâlâm, dan tasawuf filosofis atau Wujudiah. Oleh pengikut ajarannya,
Mullâ Sadrâ diklaim telah mampu menuntaskan problem-problem yang diusung
berbagai aliran pemikiran tersebut557.
Dalam pandangan Murtadha Muthahari, beberapa bidang ilmu pengetahuan
tidak dapat diintegrasikan (diselaraskan) satu sama lain. Akan tetapi, antara tasawuf
filosofis dan filsafat Islam (hikmah) dapat diselaraskan. Hal ini karena filsafat Islam
adalah berfokus pada kajian metafisika sebagaimana filsafat yang dibangun Mullâ
Sadrâ dan filosof muslim sebelumnya. Bahkan, menurut Murtadha Mutahhari, makna
al-hikmah al-muta'alliyah sebagai filsafat tertinggi atau al-hikmah ilahiyah meskipun
dibangun secara sistematis oleh Mullâ Sadrâ, sebenarnya sistem tersebut telah
dimulai oleh Ibn Sînâ558. Untuk memperjelas pandangan Murtadha Muthahhari, perlu
diingat kembali bahwa Ibn Sînâ pada periode akhir kehidupannya menulis sebuah
karya berjudul al-Hikmah al-Masyriqiyyah sebagai sebuah sistem filsafat Ilahiah.
Meskipun demikian, sebagaimana dikatakan Shams Inati, kajian Ilahiah oleh Ibn Sînâ
telah dimulai dalam karyanya al-Isyarat wa al-Tanbîhât’559.
Ajaran Mullâ Sadrâ tidak terlalu populer di Indonesia. Meskipun demikian,
kajian mengenai pemikiran Mullâ Sadrâ mulai banyak dilakukan. Hasan Bakti
Nasution menulis disertasinya berjudul “Hikmah Muta'alliyah: Analisa Terhadap
Proses Sintesa Filosofis Mullâ Sadrâ” pada 2001 dengan promotor Dr. Jalaluddin
Rakhmat dan Dr. Mulyadhi Kartanegara. Nasution mengaku belum ada disertasi yang
553 Cipta Bakti Gama, “Reduksionisme Eksplanatif Untuk Antropologi Transendental
Jawadi Amuli,” Kanz Philosophia : A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism 5, no. 2
(2015): 147–164. 554 Nasr, Islamic Philosophy From Its Origin to the Present, 108. 555 Gama, Filsafat Jiwa: Dialektika Filsafat Islam, Dan Filsafat Barat Kontemporer,
112–113. 556 Nurcholish Madjid, “Pemikiran Filsafat Islam di Dunia Modern: Problem
Perbenturan antara Warisan Islam Dan Perkembangan Zaman,” Jurnal Al-Hikmah 6, no. 1
(1992): 70. 557 Murtadha Muthahhari, Filsafat Hikmah: Pengantar Pemikiran Sadra (Bandung:
Mizan, 2002), 77–78. 558 Murtadha Muthahhari, Filsafat Hikmah…, 71–72. 559 Inati, “Ibn Sina,…” 245.
141
meneliti tentang pemikiran Mullâ Sadrâ. Selanjutnya, pemikiran Mullâ Sadrâ diteliti
oleh Syaifan Nur560. Setelah itu, muncul beberapa penelitian atas pemikiran Mullâ
Sadrâ.
Setelah Mullâ Sadrâ, filsafat dikembangkan oleh pengikutnya, seperti Mulla
Hadî Sabzawarî. Syarah al-Mandzumah merupakan salah satu karya penting Mullâ
Hadî Sabzawarî561. Selain memuat kajian metafisika mendalam, Syarah al-
Mandzumah ditulis dengan bahasa Arab yang indah. Dengan bahasa yang indah itu,
kajian atas pemikiran Mullâ Hadî Sabzawarî tidak hanya di bidang metafisika, tetapi
juga ilmu kebahasaan562. Kehadiran Mullâ Hadî Sabzawarî sangat berpengaruh atas
perkembangan pemikiran Mullâ Sadrâ selanjutnya. Kedalaman kajian metafisika dan
keindahan bahasa yang dimiliki Mullâ Hadî Sabzawarî sangat memengaruhi
pandangan metafisika dan penulisan sajak-sajak Allama Sir Muhammad Iqbal.
B. Gagasan Utama Ajaran Mullâ Sadrâ
Pemikiran filsafat Mullâ Sadrâ dapat dikatakan sebagai salah satu gagasan
penting dalam diskursus filsafat. Konsep ajarannya, antara lain, memperhatikan
segenap daya jiwa yang dimiliki manusia. Gagasan tersebut memperhatikan daya
jiwa dalam kehadirannya sebagai persepsi indrawi. Dalam hal ini, ajaran Mullâ Sadrâ
memperhatikan kesesuaian perspektif lahir dipahami melalui daya jiwa dalam ranah
indrawi, daya jiwa dalam inteleksi dan imajinasi, dan daya batin jiwa dalam
menemukan kebenaran sejati. Titik tekan pemikiran Mullâ Sadrâ adalah kemampuan
jiwa dalam menyingkap pengalaman spiritual. Sebab itulah, Mullâ Sadrâ menjadikan
kemampuan penyingkapan makna batin sebagai fokus utamanya dengan
mengedepankan pentingnya kesesuaian penyingkapan batin dengan aspek rasional
dan indrawi. Filsafat Mullâ Sadrâ yang dibangun berdasarkan pemikirannya yang
menyeluruh dapat dikatakan sangat baik karena dia telah menyintesis pemikiran para
filosof, teolog, dan sufi sepanjang pemikiran Islam sebelumnya563.
Dalam filsafat Mullâ Sadrâ, epistemologi dan ontologinya hampir tidak dapat
dipisahkan. Muhsin Labib564 mengatakan, epistemologi dalam filsafat Mullâ Sadrâ
berlaku seperti jalur masuk untuk pembahasan ontologi. Lagi pula, apabila
pengetahuan berlaku sebagai entitas (mawjûd, ekstensi, maujud) berarti merupakan
560 Syaifan Nur, Filsafat Hikmah Mulla Sadra (Yogyakarta: Rausyan Fikr, 2012), 15. 561 Muhammad Kamal, “Existence and Non-Existence in Sabzawari’s Ontology,”
Sophia 51, no. 3 (September 14, 2012): 395–406, http://link.springer.com/10.1007/s11841-
011-0283-z. 562 W. Ivanow, “Some Poems in the Sabzawari Dialect,” Journal of the Royal Asiatic
Society of Great Britain & Ireland 59, no. 1 (January 15, 1927): 1–41,
https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0035869X00056914/type/journal_articl
e. 563 Kerwanto, “Epistemologi Tafsir Mulla Sadra,” Jurnal THEOLOGIA 30, no. 1
(June 10, 2019): 23–50, http://journal.walisongo.ac.id/index.php/teologia/article/view/3238. 564 Muhsin Labib, Pemikiran Filsafat Ayatullah M.T. Misbah Yadzi (Jakarta: Sadra
Press, 2011), 146.
142
bagian dari ontologi. Namun, pemisahan dalam kajian ini tetap diperlukan565.
Fungsinya adalah untuk menyesuaikan skema ajaran Mullâ Sadrâ.
Dalam sistem metafisikanya, sebagaimana disepakati para pengulas pemikiran
Mullâ Sadrâ, terdapat beberapa sistem utama ontologi ajaran Mullâ Sadrâ, antara lain,
ashalat al-wujûd (kemendasaran wujud), tasykik al-wujûd (gradasi wujud), dan al-
harâkah al-jawhariyah (gerak substansi)566. Sementara dalam epistemologinya
adalah pembahasan tentang konsep dan sistem perolehan pengetahuan. Konsep-
konsep ini dibahas pada bagian selanjutnya. Dalam bagian ini, hanya mencoba
pembagian kajian ontologi dan epistemologi Mullâ Sadrâ yang menjadi dasar
pembangunan pemikirannya.
1. Ontologi Pemikiran Mullâ Sadrâ
Sistem penting dalam pemahaman ontologi Mullâ Sadrâ adalah tentang
kemendasaran wujud (ashalat al-wujûd). Dalam sistem ashalat al-wujûd, membahas
tentang bagaimana suatu entitas yang diamati pada realitas eksternal membentuk
dualitas di dalam pikiran, yakni ke-apa-annya (mâhiyâh) dan ke-ada-annya (wujûd).
Padahal, dari wujûd dan mâhiyâh itu, acuan realitasnya hanya satu. Hal tersebut
karena pada realitas tidak terbentuk dari dualitas, tetapi satu entitas tinggal (tidak
rangkap)567. Misalnya, sebuah meja pada realitas eksternal adalah satu entitas tunggal,
tidak rangkap. Akan tetapi, ketika dianalisis dalam persepsi mental, menjadi dualitas,
yakni ke-apa-annya yang menjadikannya sebagai suatu entitas, dan ke-ada-annya.
Demikian setiap entitas yang masuk persepsi mental akan menjadi dualitas sehingga
dapat dianalisis, seperti “meja ada”, “lemari ada”, “manusia ada”, dan seterusnya568.
Problem dualitas konseptual dari satu entitas tunggal ini kali pertama
disinggung Aristoteles, kemudian direspons Al-Farabî569. Lalu, diperdalam Ibn Sînâ,
Syihab al-Dîn al-Suhrawardî, dan Mullâ Sadrâ. Oleh Ibn Sînâ dikatakan bahwa yang
mendasar adalah ke-ada-annya (wujûd). Namun, dia tidak mempertegas apakah
wujûd sebagai yang mendasar itu berada pada status mental (dhihnî) atau pada realitas
eksternal (kharîjî). Syihab al-Dîn al-Suhrawardî menganggap, Ibn Sînâ berpendapat,
wujûd yang mendasar dalam ranah konseptual. Syihab al-Dîn al-Suhrawardî
menyanggahnya dengan berpendapat bahwa yang mendasar itu adalah mâhiyâh.
565 Dalam hal ini, pembahasan epistemologi Mullâ Sadrâ menjadi sulit dipisahkan
dengan pembahasan ontologi. Karena Mullâ Sadrâ sendiri sebenarnya tidak bermaksud
melakukan klasifikasi terhadap ranah ontologi dan ranah epistemologi. Ketika dia
menggunakan argumentasi-argumentasi burhanî, di sanalah wilayah dapat disebut
epsitemologi. Kesulitan membedakan dimensi epistemologi dan dimensi ontologi ajaran
Mullâ Sadrâ awalnya ditemukan oleh Muhammad Taqi Misbah Yazdi dan disampaikan oleh
Muhsin Labib ketika mengkaji aliran filsafat al-Hikmah al-Muta’alliyah, khususnya
pemikiran Muhammad Taqi Misbah Yazdi sebagai pengikut al-Hikmah al-Muta’alliyah.
Labib, Pemikiran Filsafat Ayatullah M.T. Misbah Yadzi, 144-145. 566 Seyyed Hossein Nasr, Al-Hikmah Al-Muta’alliyah Mulla Sadra: Sebuah Terobosan
dalam Filsafat Islam (Jakarta: Sadra Press, 2017), 97–98; Nur, Syaifan, Filsafat Hikmah
Mulla Sadra (Yogyakarta: Rausyan Fikr, 2012), 86–87. 567 Nasr, Islamic Philosophy From Its Origin to the Present…, 196. 568 Izutsu, Struktur Metafisika Sabzawari…, 133–134. 569 Izutsu, Struktur Metafisika Sabzawari…, 93.
143
Syihab al-Dîn al-Suhrawardî mengatakan, proposisi “meja itu ada”, “lemari itu ada”,
“manusia itu ada”, selalu menunjukkan bahwa “ada” atau wujûd dalam setiap
proposisi hanya menjadi predikat sehingga yang mendasar adalah mâhiyâh (ke-apa-
an)570.
Perdebatan mana yang primer dan mana yang sekunder dalam filsafat Islam
menjadi lebih serius dimulai oleh Nasr al-Dîn Thusî. Dalam hal ini, Nasr al-Dîn Thusî
memulai persoalan ini dengan memperjelas inti yang sebelumnya disalahpahami dari
filsafat Ibn Sînâ. Sebelumnya, para filosof menganggap, dalam pemikiran Ibn Sînâ,
separasi antara wujûd dan mâhiyâh adalah pada ranah aktual. Nasr al-Dîn Thusî
memperjelas bahwa separasinya adalah pada ranah mental. Karena itu, sebelum Nasr
al-Dîn Thusî, banyak filosof menjadi salah paham atas pemikiran Ibn Sînâ. Setelah
Nasr al-Dîn Thusî, diskursus mengenai separasi antara mâhiyâh dan wujûd menjadi
makin gencar. Toshihiko Izutsu mengatakan, terdapat tiga golongan dalam hal ini.
Pertama adalah yang meyakini wujûd yang mendasar. Mereka adalah Ibn Sînâ dan
Mullâ Sadrâ. Kedua adalah kalangan yang meyakini mâhiyâh yang mendasar. Mereka
adalah Syihab al-Dîn al-Suhrawardî dan Mir Damad. Ada juga filsuf yang meyakini
wujûd dan mâhiyâh keduanya mendasar. Akan tetapi, argumentasi ini tidak populer.
Kemendasaran wujûd yang dimaksud Ibn Sina dan Mullâ Sadrâ berbeda. Bagi
Ibn Sina, wujûd memang mendasar pada realitas, tetapi tiap-tiap wujûd itu berbeda
menurut perbedaan mâhiyâh-nya. Sementara bagi Mullâ Sadrâ, wujûd itu mendasar
pada realitas eksternal dan sekaligus tunggal melingkupi segala sesuatu. Mullâ Sadrâ
sepakat dengan Ibn Sînâ dalam pembedaan wujûd dengan mâhiyâh pada ranah
konseptual. Ketika masuk ke ranah konseptual, wujûd menjadi mâhiyâh dan
mendasari sehingga wujûd menjadi tambahan bagi mâhiyâh. Sementara pada realitas
eksternal, wujûd yang mendasar571.
Syihab al-Dîn al-Suhrawardî menyatakan mâhiyâh yang menjadi dasar realitas.
Karena bila wujûd yang mejadi dasar realitas, wujûd itu membutuhkan wujûd yang
lain sebagai sebab. Menurut Mullâ Sadrâ, mâhiyâh itu tidak nyata. Seandainya pun
nyata, tetap tidak dapat menyatukan realitas karena perbedaan antarentitasnya
sehingga yang nyata yang menyatukan realitas adalah wujûd. Syihab al-Dîn al-
Suhrawardî juga mengatakan bahwa wujûd hanya ada pada ranah mental dan ia
menjadi tambahan bagi mâhiyâh. Mullâ Sadrâ membantahnya dengan menyatakan
bahwa esensi sebagaimana esensi itu sendiri tidak akan dapat diketahui karena tidak
memberikan efek. Yang memberikan efek itu adalah eksistensi. Berarti, eksistensinya
yang nyata pada realitas, bukan mâhiyâh572.
Syihab al-Dîn al-Suhrawardî juga mengatakan bahwa terdapat hubungan
antara wujûd dan mâhiyâh sebagai satu kesatuan ontologis. Mullâ Sadrâ
membantahnya dengan mengatakan bahwa dualitas wujûd dan mâhiyâh ada ada pada
pikiran. Mâhiyâh itu sendiri tidak punya gradasi. Yang punya gradasi adalah wujûd
570 Izutsu, Struktur Metafisika Sabzawari…, 105–107. 571 Fathul Mufid, “Perkembangan Paradigma Epistemologi dalam Filsafat Islam,”
Ulumuna (2013) 19-40. 572 Izutsu, Struktur Metafisika Sabzawari…, 114.
144
seperti lebih dahulu disebut sebab dan lebih kemudian disebut akibat573. Karena
berpendapat bahwa yang lebih mendasar adalah mâhiyâh, Syihab al-Dîn al-
Suhrawardî disebut sebagai penganut ashalat al-mâhiyâh, yakni filsafat yang
meyakini bahwa mâhiyâh-lah yang menjadi dasar pembentuk realitas. Menurut
Syihab al-Dîn al-Suhrawardî, dasar pembentuk realitas adalah mâhiyâh574.
Mullâ Sadrâ hadir menyanggah pandangan Syihab al-Dîn al-Suhrawardî
dengan mengatakan bahwa yang mendasar itu adalah mâhiyâh, itu benar. Akan tetapi,
hanya dalam ranah mental. Sementara pada realitas eksternal itu, yang mendasar
adalah wujûd. Namun yang perlu ditegaskan adalah, para filosof sebelum Mullâ Sadrâ
tidak mempersoalkan mana yang mendasar antara wujûd dan mâhiyâh, dalam arti
bahwa mereka tidak melihat konsekuensi-konsekuensi dari perbedaan pandangan
tersebut. Barulah Mullâ Sadrâ yang menganggap prinsip tersebut sebagai sesuatu
yang serius karena menjadi bagian dari bagaimana realitas itu tegak karena mana
yang ashil itulah yang menjadi dasar realitas. Sementara yang 'itibar itu tidak nyata,
hanya proyeksi mental (inteleksi)575.
Dalam pandangan Mullâ Sadrâ, mâhiyâh tidak dapat menjadi fondasi bagi
realitas eksternal karena tidak dapat menjadi penghubung atau tidak memiliki
penghubung antara satu entitas dan entitas yang lain. Maka dari itu, konsekuensinya
realitas eksternal harus merupakan susunan antar mâhiyâh. Suhrawardi tentunya akan
menjawab problem ini dengan mengatakan bahwa entitas-entitas di alam tersebut
adalah kegelapan mutlak, sementara yang nyata hanya cahaya576.
Berbeda dengan Syihab al-Dîn al-Suhrawardî, Mullâ Sadrâ berpandangan
realitas eksternal yang dapat dikenali dan dipersepsikan ini adalah realitas yang nyata,
bukan bayangan (tasawuf filosofis), bukan ketiadaan (panteis), bukan ilusi (sofis),
dan bukan kegelapan (isyraqiyyah). Syihab al-Dîn al-Suhrawardî mengatakan bahwa
mâhiyâh menjadi yang mendasari realitas dengan gambaran bahwa pada setiap
komposisi “meja itu ada” dan sebagainya yang lebih dahulu hadir selalu adalah
mâhiyâh, disusul oleh wujûd sebagai predikasi, itu benar dalam realitas mental577.
Akan tetapi, untuk membuktikan mana yang fundamental, antara wujûd dan mâhiyâh
sehingga dapat dipastikan manakah yang yang menjadi realitas sejati yang mengisi
ranah eksternal adalah melalui pembuktian manakah yang memberikan efek578.
Pertama-tama, perlu dibedakan antara ranah mental dan ranah eksternal. Pada
ranah mental, sesuatu tidak memberikan efek. Sementara pada realitas eksternal,
sesuatu tersebut memberikan efek. Api pada ranah mental tidak membakar. Api pada
ranah eksternal itu membakar. Selanjutnya, perlu dibuktikan apakah yang mengisi
573 Abdolmajid Hakimelahi dan Basrir Hamdani, “Belief in God by Intuitive
Knowledge,” Kanz Philosophia : A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism 6, no. 1
(June 13, 2016): 73, http://journal.sadra.ac.id/index.php/kanzphilosophia/article/view/172. 574 Nur, Filsafat Hikmah Mulla Sadra…, 152–153. 575 Nasr, “Existence (Wujūd) and Quiddity (Māhiyyah) in Islamic Philosophy.”…,
409-428, 576 Khalid Al-Walid, Perjalanan Jiwa Menuju Akhirat (Jakarta: Sadra Press, 2012), 46. 577 Mehdi Amin Razavi, Suhrawardi and the School of Illumination, (London:
Routledge, 2014), 99-100 578 Izutsu, Struktur Metafisika Sabzawari…, 144.
145
realitas eksternal itu? Kalau bukan wujûd, tentunya mâhiyâh. Karena entitas realitas
itu tunggal, tidak rangkap.
Argumentasi yang dikemukakan pengikut fundamentalitas wujûd sebagaimana
Sayyid Hussîn Thabattâbâ'i adalah, apabila mâhiyâh tanpa melibatkan wujûd, tidak
ada perbedaan apakah pada realitas eksternal maupun ranah mental. Namun yang
terjadi adalah, terdapat perbedaan antara mâhiyâh pada realitas eksternal dan mâhiyâh
pada ranah mental. Perbedaannya seperti mâhiyâh api. Bila api pada realitas eksternal
dengan api pada ranah mental adalah sama, seharusnya api pada ranah mental juga
membakar. Namun, yang terjadi tidak demikian sehingga argumentasi ini menjadi
bukti bahwa ternyata yang memberikan efek itu adalah adalah wujûd-nya, bukan
mâhiyâh-nya. Karena itu, yang mengisi realitas eksternal adalah wujûd, bukan
mâhiyâh. Mâhiyâh hanya menjadi pembatasan bagi wujûd sehingga dapat
teridentifikasi melalui analisis mental. Ketika berada pada ranah mental, yang
mendasari adalah mâhiyâh, sementara wujûd hanya menjadi predikat bagi
mâhiyâh579.
Dari segi istilah, kata mâhiyâh berasal dari kata mâ dan huwâ. Istilah itu
sebagai usaha mencari padanan istilah Yunani, quid dan est yang berarti sebuah
istilah untuk sesuatu yang teridentifikasi ada (esse) secara sederhana (haliyah
basithah). Konsepsi suatu objek oleh mental (pikiran) disebut ekstensi. Setiap
konsepsi yang dibentuk pikiran mustahil hanya satu entitas karena setiap entitas harus
nonkontradiksi. Mâhiyâh terbagi menjadi mâhiyâh makhluthah, yakni mâhiyâh yang
berhubungan dengan suatu objek eksternal (ekstensi, mawjûdat). Selanjutnya,
mâhiyâh mujarrad, yakni konsep abstrak yang lepas dari hubungannya dengan
ekstensi, tetapi masih memungkinkan diterapkan pada suatu ekstensi. Terakhir,
mâhiyâh muthlaq, yakni mâhiyâh yang sama sekali tidak berhubungan dengan
penerapannya pada ekstensi.
Mâhiyâh itu ketika ingin ditemukan lokusnya pada realitas eksternal,
membutuhkan sesuatu yang lain agar dapat teraktualisasi. Mengaktualnya mâhiyâh
adalah karena aktualitas wujûd. Sebenarnya, mâhiyâh itu sendiri hanyalah produksi
mental yang dapat dipersepsi secara aktual karena adanya wujûd pada realitas
eksternal. Mâhiyâh pada dirinya sendiri tanpa melibatkan wujûd, berada pada status
keberadaan dan ketiadaan. Hanya dengan memberikan wujûd kepada mâhiyâh maka
menjadilah ia dapat dilibatkan dalam prinsip identitas. Karena yang memberikan
identitas kepada mâhiyâh adalah wujûd, tentu wujûd yang mendasari realitas580.
Wujûd adalah sesuatu yang tunggal dan menjadi dasar ('ashil) bagi realitas.
Sementara mâhiyâh adalah pembatasan-pembatasan mental bagi wujûd. Mâhiyâh
hanyalah bentukan mental ('itibarî) untuk membatasi (menangkap) realitas sehingga
meskipun bagi mental mâhiyâh itu mendasar, pada realitas, wujûd-lah yang
mendasar, menyeluruh, dan sederhana581.
Mullâ Sadrâ menerima prinsip pembagian wujûd Ibn Sînâ. Tidak ada
pembahasan wujûd melebihi Wajib al-Wujûd lî nafsîhî, wajib al-wujûd li ghayrihî,
mumkîn wujûd, dan mumtanî al-wujûd. Gradasi wujûd yang dibuat Mullâ Sadrâ
579 Thabâthabâ’î, Bidâyah al-Ḥikmah…, 15–17. 580 Mulla Sadra, Al-Masya’ir (Teheran: The Institute for Culturan Studies, 1992), 10. 581 Mulla Sadra, Al-Masya’ir…, 8-9.
146
diinspirasikan dari illuminasi cahaya dari pemikiran Syihab al-Dîn al-Suhrawardî.
Mullâ Sadrâ mengganti esensi cahaya sebagai yang prinsipiel dengan eksistensi
(wujûd) sebagai yang prinsipiel. Akan tetapi, gagasan ontologi Mullâ Sadrâ sangat
dekat dengan Wujudiah Ibn ‘Arabî. Hal ini karena Wujudiah adalah ajaran tasawuf
filosofis, sementara Mullâ Sadrâ dianggap sedang membangun filsafat maka dia tidak
dapat menerima Wujudiah, kecuali bâsîth al-haqiqah kullî al-asya’ dan tasykîk al-
wujûd (gradasi eksistensi)582.
Konsep tasykîk al-wujûd diinspirasikan dari sistem manifestasi cahaya dari
ajaran Syihab al-Dîn al-Suhrawardî. Mullâ Sadrâ mengganti prinsipalitas mâhiyâh
menjadi prinsipalitas wujûd. Lalu, menyatakan bahwa wujûd itu satu dan bergradasi.
Dalam sistem gradasi, kemajemukan itu nyata sekaligus ketunggalan itu nyata. Inilah
yang disebut ambiguitas sistem tasykîk. Dalam sistem ini, ketunggalan mengalir
dalam keberagaman dan keberagaman kembali kepada ketunggalan. Perbedaan
terletak pada kesamaan dan kesamaan terletak pada perbedaannya. Perbedaannya
adalah pada wujûd dan persamaannya adalah pada wujûd.
Kesatuan wujûd yang bergradasi dipandang Mullâ Sadrâ sejalan dengan
prinsipnya bahwa substansi itu bergerak583. Pandangan ini berbeda dengan Ibn Sînâ
yang berpandangan bahwa substansi itu tetap dan menopang aksiden yang bergerak.
Gerak substansi adalah revolusi yang dicetuskan Mullâ Sadrâ dalam filsafat.
Sebelumnya, para filosof menerima prinsip Aristotelian yang menegaskan gerak
hanya terjadi pada level aksiden. Sementara bagi Mullâ Sadrâ, perubahan aksiden
adalah karena substansinya yang bergerak. Gerak substansi Mullâ Sadrâ ini
dipengaruhi gerak cinta dalam 'irfân, khususnya ajaran Ibn ‘Arabî. Dengan gerak
substansi maka meniscayakan perubahan satu entitas wujûd menjadi entitas wujûd
lainnya. Pandangan ini sejalan dengan prinsip tasykîk al-wujûd584.
Perubahan pada aksiden adalah kuantitas, kualitas, posisi, dan tempat. Ini
merupakan pandangan Peripatetik yang diterima Mullâ Sadrâ. Akan tetapi, dia tidak
sepandangan dengan Peripatetik yang tidak menerima perubahan substansi. Bagi
Mullâ Sadrâ, segala entitas memiliki pergerakan pada substansinya. Gerak ini adalah
pergerakan menuju kesempurnaan. Pada dirinya sebagai aktualitas, wujûd jasmani
sekaligus adalah potensialitas. Potensialitas ini menjadi aktual ketika jiwa terlepas
dari jasad. Jiwa yang telah terlepas dari jasad adalah aktualitas murni585. Karena gerak
substansi adalah proses menuju kesempurnaan, mustahil terjadi gerak terbalik.
Sesuatu yang dari lebih sempurna menjadi kurang sempurna itu mustahil. Sebab
582 Benny Susilo, “Teori Gradasi : Komparasi Antara Ibn Sina, Suhrawardi Dan
Mulla Sadra,” Kanz Philosophia : A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism 5, no. 2
(December 29, 2015): 159,
http://journal.sadra.ac.id/index.php/kanzphilosophia/article/view/139. 583 Mullâ Sadrâ, Al-Hikmah Muta’aliyyah Fî Al-Asfâr Al-’Aqliyyah Al-Arba’ah Vol.
3, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-’Arabi, 2002), 249. 584 Susilo, “Teori Gradasi : Komparasi Antara Ibn Sînâ , Suhrawardi Dan Mulla
Sadra,”…, 159. 585 Reza Akbarian, Trans-Subtantial Motion and Its Philosophical Consequencess Di
Dalam Mullâ Sadrâ and Transendent Philosophy; Islam-West Philosophical Dialog, Shadra
Islamic Philosophical Institute Publication (Teheran, 1999), 182–183.
147
gerak menuju kesempurnaan itu dinamis dan aktualitas sejati adalah setelah jiwa
melepaskan diri dari jasad maka bagi Mullâ Sadrâ reinkarnasi itu mustahil586.
2. Epistemologi Pemikiran Mullâ Sadrâ
Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang sumber dan cara
memperoleh pengetahuan. Mullâ Sadrâ membagi ilmu berdasarkan empat tinjauan.
Pertama adalah fisika, kedua adalah metafisika yang mencakup ontologi (kenabian
dan eskatologi), ketiga logika, dan keempat matematika. Pembagian ini mirip seperti
yang dilakukan Ibn Sina, kecuali Mullâ Sadrâ menempatkan kajian jiwa dalam
metafisika dan Ibn Sina mengkajinya pada bagian khusus. Ditinjau dari segi
sumbernya, Mullâ Sadrâ membagi ilmu ke dalam ilmu 'aqliyyah dan ilmu syar'iyyah.
Ilmu ‘aqliyah adalah ilmu yang berdasarkan penemuan manusia. Sementara ilmu
syar'iyyah adalah ilmu yang diperoleh melalui wahyu587.
Ada juga ilmu dibagi menjadi ilmu yang kekal dan tidak kekal. Ilmu tidak kekal
seperti ilmu terkait kebahasaan, seperti ilmu musik, ma'ani, bayan, badi', dan logika.
Ilmu tidak kekal lainnya, seperti ilmu pertukangan, pertanian, bangunan, tulis-
menulis, dan politik. Ada pula ilmu tentang definisi dan argumentasi, ilmu tentang
ukuran dan bilangan, kimia, astronomi, biologi, dan kedokteran. Sementara ilmu
kekal terkait dengan rukun iman, musyahadah588.
Menurut Mullâ Sadrâ, ditinjau dari cara memperolehnya, pengetahuan terbagi
menjadi pengetahuan presentasi (hudhûrî) dan pengetahuan representasi (hushûlî).
Ilmu hudhûrî adalah ilmu yang diperoleh melalui penyingkapan langsung, tanpa
perantara, seketika seperti kilatan cahaya. Sementara ilmu hushûlî adalah ilmu yang
diperoleh melalui proses inteleksi, pengindraan, dan penalaran. Ilmu hushûlî terbagi
menjadi tasawûr dan tasydiq. Mullâ Sadrâ membagi ilmu hushûlî kepada dua
kelompok, yakni naqlî dan aqlî. Ilmu naqlî ini tentunya adalah Al-Qur’an. Ilmu aqlî
terbagi menjadi ilmu empiris dan ilmu rasional. Ilmu rasional terbagi menjadi akal
sehat (common sense, lûh al-nafs), imajinasi, dan wahm (estimasi)589.
Pengetahuan presentasi diperoleh melalui pengalaman mistik ‘urafâ (kasyaf).
Pengetahuan representasi diperoleh indra dan akal (nalar). Pengetahuan melalui
pancaindra memiliki kelemahan, seperti tampak bengkoknya pena di dalam gelas
sehingga membutuhkan akal untuk membantunya590. Akal memiliki dua sistem
mendasar, yakni pembuktian melalui premis-premis universal yang niscaya diterima
akal (burhan) dan pemikiran dialektis (jadal). Dalam filsafat Islam, akal memiliki
berbagai tingkatan. Akal hayulanî adalah akal potensial rasional yang siap menerima
gambar-gambar rasional yang diberikan Akal aktif. Akal malakah adalah aktualitas
586 Mullâ Sadrâ, Al-Syawâhid al-Rubûbiyyah fî al-Manâhij al-Sulûkiyyah (Teheran:
Bustan Kitabevi, 1388H), 255. 587 Nasution, “Hikmah Muta’alliyah: Analisa Terhadap Proses Sintesa Filosofis Mulla
Sadra,”…, 18–19. 588 Nasution, “Hikmah Muta’alliyah: Analisa Terhadap Proses Sintesa Filosofis Mulla
Sadra,”…, 19. 589 Mustamin Al-Mandary, Menuju Kesempurnaan: Pengantar Pemikiran Mulla Sadra
(Polman: Rumah Ilmu, 2018), 204–205. 590 Mulyadhi Kartanegara, Menyibak Tirai Kejahilan: Pengantar Epistemologi Islam
(Bandung: Mizan, 2003), 18.
148
akal hayulanî. 'Aql bî al-fi’lî, yaitu penggerak akal hayulanî menjadi aktual. Akal
mustafad adalah kesempurnaan aktualitas akal hayulanî yang merupakan bentuk
gambar murni sehingga mampu menangkap gambar murni dan telah dapat
berhubungan dengan Akal aktif yang merupakan gambar tetap murni. Oleh karena
itu, dalam capaian akal mustafad telah dapat dilihat gambar-gambar abstrak yang
dapat saja dalam gambar konkretnya belum teraktualisasi.
Ibn Sinâ berpendapat, di atas akal mustafad terdapat akal suci (al-'aql al-qudsî)
yang hanya dimiliki para nabi. Para filosof sepakat bahwa akal memiliki peran
signifikan dalam perolehan pengetahuan. Akal suci ini disebut juga dengan intuisi
(hudhûrî). Syihab al-Dîn al-Suhrawardî mengatakan, para muta'allih adalah mereka
yang mampu mencapai intuisi (dzauqî) sekaligus mampu membuktikan pengalaman
mereka melalui akal (bahtsi)591.
Menurut epistemologi Mullâ Sadrâ, pengetahuan adalah hadirnya yang
diketahui kepada yang mengetahui. Pengetahuan itu sifatnya immateri. Objek
eksternal pada alam materi hanya persiapan bagi turunnya pengetahuan yang
sebenarnya immateri pada yang mengetahui (melalui jiwa) yang juga immateri.
Pengetahuan adalah keyakinan yang sesuai dengan realitas pengetahuan yang
dimaksud dalam konteks ini adalah pengindraan sederhana yang belum menyentuh
ranah pengetahuan terkait dengan proposisi-proposisi pikiran.
Pengetahuan representasi (hushûlî) adalah pengetahuan yang hadir dari luar
diri dalam bentuk aksiden-aksidennya. Antara yang mengetahui dan yang diketahui
tentunya adalah berbeda. Dalam pengetahuan representasi, terdapat tiga hal, yakni
subjek yang mengetahui, objek yang diketahui, dan konsep pengetahuan592. Dalam
pengetahuan representasi, terdapat dua jenis pengetahuan, yakni pengetahuan tentang
hal konkret (partikular, juz'i) dan pengetahuan tentang yang umum (abstrak, kullî).
Sayyid Hussîn Thabattâbâ'i mengatakan, kemampuan abstraksi partikular kepada
universal merupakan karakteristik akal. Kemampuan ini membuat manusia dapat
menghimpun atau menyimpan pengetahuan sebanyak-banyaknya tanpa kesulitan593.
Empirisme mengatakan bahwa universal itu adalah korupsi atas partikular.
Analoginya permukaan koin yang kabur menyebabkan partikularitas koin menjadi
samar dan kembali kepada universalitas594. Sementara epistemologi Mullâ Sadrâ
mengatakan bahwa universalitas itu merupakan tingkatan partikularitas yang lebih
tinggi. Universalitas adalah kesempurnaan partikular595.
Dalam filsafat Islam, universal terbagi menjadi universal pertama dan
universal kedua. Universal pertama adalah hubungan langsung antara realitas
eksternal dan pikiran596. Misalnya, menghubungkan universal manusia dengan
591 Ismail Fahmi Arrauf Nasution, Filsafat Ilmu Pengetahuan, (Lhokseumawe: Unimal
Press, 2018), 5–6. 592 Nasution, Filsafat Ilmu Pengetahuan…, 1–15. 593 Thabâthabâ’î, Nihayah Al-Ḥikmah, (Qum: Muʽassasah an-Nasyr al-Islâmî, 1428),
349. 594 Bertrand Russell, History of Western Philosophy (London: George Allen and
UNWIN, 1946), 556. 595 Kalin, Knowledge in Later Islamic Philosophy…, 149. 596 Kalin, Knowledge in Later Islamic Philosophy…, 123–124.
149
Ahmad, Zaid, dan Budi. Ranah ini disebut dengan ma'qulat al-awwal atau primary
intelligable597. Universal kedua adalah konsep-konsep universal yang tidak memiliki
acuan partikularitas di alam eksternal. Misalnya, konsep “genus” dan konsep
“spesies”. Tidak ada benda atau apa pun yang bisa disebut atau ditunjuk sebagai
“genus” dan “spesies” di realitas eksternal. Konsep-konsep universal ini hanya
terdapat pada pikiran. Konsep-konsep ini adalah ranah ilmu logika. Ranah ini disebut
ma'qulat tsanî mantiqî atau logical secondary intelligable. Ada pula yang disebut
dengan ma'qulat tsanî falsafî atau philosophical secondary intelligable, yakni
konsep-konsep universal yang dapat diacu para partikularitas di alam eksternal598.
Ranah ini berada dalam wilayah ilmu filsafat dan matematika. Misalnya, konsep
segitiga dapat diacu pada salah satu piramida di Mesir.
Perolehan pengetahuan representasi ditempuh melalui konsepsi (tasawwur)
dan konfirmasi (tasydiq). Konsepsi adalah munculnya pemahaman tentang konsep,
namun oleh subjek yang mengetahui belum mengonfirmasi konsepsi tersebut.
Konfirmasi bisa dalam bentuk afirmasi (ijabah) ataupun negasi (salb)599.
Konsepsi terbagi kepada konsepsi mandiri, seperti “manusia”, “hewan”;
konsepsi yang memiliki differensia, seperti “hewan yang berpikir”; konsepsi berelasi
perintah, seperti “pukullah”, “pergilah”; dan konsepsi berelasi berita, seperti “Ahmad
berdiri”, “Ahmad berjalan”. Konsepsi adalah kaitan antara mental dan eksternal.
Sementara afirmasi adalah penilaian afirmatif atau negatif tentang kepastian positif
atau negatifnya hubungan konsepsi dan realitasnya. Afirmasi negatif meniscayakan
hadirnya dua konsep, seperti “Ahmad” dan “berdiri”. Hal ini karena negatifnya
Ahmad berdiri bukan konsepsi sebab tidak ada konsepsi dari negativitas realitas.
Sementara afirmasi positif meniscayakan tiga konsep, yakni “Ahmad”, “berdiri”, dan
“Ahmad berdiri”600.
Sistem pengetahuan representasi berasal dari Ibn Sînâ dan diterima Syihab al-
Dîn al-Suhrawardî dalam skema al-Hikmah al-Masya’iyyah. Dalam sistem logika
modern, juga dibedakan antara makna dan kebenaran. Makna hanya sebuah konsep
atau pernyataan yang hanya diperlukan akurasi logika. Sementara kebenaran adalah
sesuainya makna dengan realitas601.
Pembagian lainnya dalam epistemologi Islam, khususnya dalam ajaran Mullâ
Sadrâ adalah ilmu yang diperoleh tanpa melalui observasi atau dapat dipahami secara
langsung karena merupakan karakteristik alami akal, seperti mengetahui keseluruhan
lebih besar daripada sebagian. Jenis ilmu ini disebut badihî. Sementara ilmu yang
baru hadir setelah melalui observasi disebut dengan nazharî602.
Terdapat beberapa bagian ilmu badihî, yakni al-mahsusat, yakni aksioma yang
didapatkan berdasarkan bantuan indra; al-mutawattirat, yakni aksioma yang
didapatkan berdasarkan bantuan eksperimen; al-fitriyat, yakni pengetahuan yang
didapatkan melalui intuisi; dan al-awwaliyat, yakni pengetahuan yang diperoleh
597 Miswari, Filsafat Terakhir…, 189. 598 Kalin, Knowledge in Later Islamic Philosophy…, 161–163. 599 Miswari, Filsafat Pertama, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), 23–24. 600 Miswari, Filsafat Pertama, 24–25. 601 Kalin, Knowledge in Later Islamic Philosophy…, 160. 602 Kalin, Knowledge in Later Islamic Philosophy…, 169–170.
150
tanpa bantuan realitas eksternal. Badihî atau aksioma adalah pengetahuan alami akal
yang normal603.
Setiap proposisi dari aksioma itu niscaya benar, tidak kontradiktif,
pertentangan yang muncul dari dua konsepsi dikembalikan kepada realitasnya.
Misalnya, pertentangan antara “manusia” dan “nonmanusia” maka manusia
dikembalikan kepada eksistensinya dan nonmanusia dikembalikan kepada
eksistensinya. Karakteristik badihî adalah tunggal, tidak rangkap, terlihat langsung,
tidak membutuhkan definisi, niscaya, meyakinkan, dan tidak sedikit pun
mengandung keraguan604.
Sementara itu, pengetahuan nazarî digunakan dalam menganalisis benda-
benda indrawi. Pengetahuan ini digunakan dalam pengamatan benda-benda sehari-
hari. Nazarî juga berlaku dalam observasi yang dilakukan para ilmuwan. Sementara
itu, ilmu hudhûrî adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung tanpa keraguan.
Tidak berlaku hukum-hukum hushûlî dalam pengetahuan ini. Pengetahuan ini
menurut Sayyid Hussîn Thabattâbâ'i terjadi dengan digambarkan sebagai relasi
iluminatif (idhafah isyraqiyyah)605.
Sayyid Hussîn Thabattâbâ'i menjelaskan, dalam filsafat Mullâ Sadrâ, realitas
itu benar-benar nyata606. Dia meyakini realitas itu dapat diketahui melalui ilmu
hudhûrî (presentasi). Ilmu representasi (hushûlî) digunakan untuk menjelaskan
pengalaman hudhûrî. Dalam filsafat Mullâ Sadrâ, ilmu hudhûrî (presentasi)
posisinya sangat penting mengingat sebagai prasyarat suatu pengetahuan sebagai
alternatif definisi yang telah dikritik Syihab al-Dîn al-Suhrawardî607. Definisi
bertujuan menjelaskan identitas sesuatu. Namun, ternyata Syihab al-Dîn al-
Suhrawardî menemukan bahwa definisi tidak dapat memenuhi persyaratan untuk
menghadirkan pemahaman terhadap sesuatu. Mendefinisikan sesuatu harus
memenuhi syarat alat definisi telah dipahami. Untuk memahami alat definisi, harus
menggunakan definisi608. Misalnya, ketika ingin mendefinisikan “manusia”,
digunakan definisi ‘manusia adalah hewan yang berpikir’. Prasyarat definisi manusia
berarti harus telah memahami “hewan” dan “berpikir”. Bila belum memahami
“hewan” dan “berpikir”, perlu mendefinisikannya. Misalnya, ‘hewan adalah makhluk
yang bergerak dengan kehendak’ Lalu, perlu telah memahami “makhluk” dan
“kehendak”. Demikian seterusnya menjadi tasalsul atau daur (dawr, ad invinitum)609.
Karena itu, definisi itu mustahil610.
603 Nasution, Filsafat Ilmu Pengetahuan…, 25. 604 Nasution, Filsafat Ilmu Pengetahuan…, 26. 605 Thabâthabâ’î, Nihayah Al-Ḥikmah…, 297. 606 Thabâthabâ’î, Bidayah Al-Ḥikmah…, 1-2. 607 Ziai, “Shihab Al-Din Suhrawardi: Founder of the Illuminationist,”…, 436. 608 Suhrawardi, “Hikmah Al-Isyrâq,”…, 6–10. 609 Daur atau tasalsul adalah hal yang tertolak dalam filsafat. Lihat, Seyyed Hossein
Nasr, “Mir Damad,” dalam An Anthology of Philosophy in Persia, Vol. 5: From the School of
Shiraz to the Twentieth Century, ed. Seyyed Hossein Nasr dan Mehdi Aminrazavi (London &
New York: I.B. Taurus Publisher, 2015), 200. 610 Husain Ziai menjelaskan dengan sangat rinci penolakan Syihab al-Dîn al-
Suhrawardî
atas definisi. Lihat, Ziai, Suhrawardi dan Filsafat Illuminasi, 225–227.
151
Kemustahilan definisi sebenarnya adalah problem filsafat. Tasawuf filosofis
telah mengatasi persoalan itu dengan ilmu hudhûrî sehingga sebenarnya yang
bertanggung jawab mengatasinya adalah filsafat. Sebab itulah, Mullâ Sadrâ
menerima ilmu hudhûrî sebagai prasyarat pengetahuan. Namun demikian, sebagai
filsuf, Mullâ Sadrâ hanya menggunakan ilmu hudhûrî sebagai alternatif definisi,
untuk mendapatkan pengetahuan awal tentang makna. Lalu, Mullâ Sadrâ dengan
konsisten mengikuti tahap-tahap epistemologi sebagaimana berlaku dalam standar
epistemologi dalam filsafat611.
Dalam pengalaman kasyaf hudhûrî, kaidah-kaidah indrawi dan inteleksi tidak
berlaku lagi. Sementara dalam ilmu hushûlî, identifikasi subjek dan objek masih
dapat berlangsung. Sementara dalam hudhûrî, identifikasi tersebut tidak dapat
terjadi612. Dalam ilmu hudhûrî, kebenaran dan kegalatan tidak berlaku karena
predikasi itu ditentukan dalam tasydîq. Sementara dalam hudhûrî, tidak melibatkan
tasawûr dan tasydîq karena itu merupakan sistem ilmu hushûlî. Mehdi Haeri Yazdi
mengatakan, ilmu hudhûrî memiliki sistemnya sendiri untuk menentukan kebenaran,
yaitu dengan pengalaman. Pengalaman itu adalah kesadaran tentang wujûd613. Dalam
sistem Mullâ Sadrâ, pengalaman wujûd adalah kebenaran mutlak yang menjadi dasar
perumusan sistem hushûlî. Tanpa didahului pengalaman hudhûrî, tidak ada apa pun
yang dapat dijadikan justifikasi atau fondasi membangun proposisi614.
Ilmu hudhûrî itu untuk mengetahui ke-ada-an (wujûd) realitas. Sementara ilmu
representasi untuk mengetahui ke-apa-an realitas (mâhiyâh, quiditty). Seyyed
Hossein Nasr menjelaskan, dalam ajaran Mullâ Sadrâ, diketahui bahwa kemajemukan
realitas alam adalah bentukan konsepsi pikiran melalui ilmu hushûlî. Namun,
sebenarnya yang mendasari realitas adalah wujûd. Sebagai suatu kajian filsafat, Mullâ
Sadrâ berusaha menjelaskan pandangan itu secara burhanî dengan mengatakan
bahwa kemajemukan itu adalah limitasi mental atas wujûd yang tinggal sekaligus
bergradasi. Ketika memersepsikan suatu ekstensi dari realitas eksternal, pikiran
membaginya pada dua aspek, yakni aspek wujûdnya, yakni keberadaan ekstensi
tersebut dan aspek mâhiyâh-nya, yakni kesesuatuan realitas tersebut615.
Filsafat Mullâ Sadrâ, sebagaimana dikatakan Ibrahim Kalin, berpandangan
ilmu hudhûrî terjadi karena sebenarnya subjek yang mengetahui ('aqil) dan objek
yang diketahui (ma’qûl) itu bersatu (ittihad). Konsep ini disebut dengan ittihad aqil
wa ma'qûl. Pengetahuan ini sama seperti cara Wajib al-Wujûd mengetahui, yaitu tidak
terpisah antara Dia sebagai subjek yang diketahui dan objek-objek pengetahuannya.
Sebenarnya, objek pengetahuan dalam sistem hushulî juga tidak merupakan dualitas
atau terpisah dengan objek-objek yang diketahui616.
611 Nur, Filsafat Hikmah Mulla Sadra…, 85. 612 Nasution, Filsafat Ilmu Pengetahuan.., 3–5. 613 Yazdi, The Principles of Epistemology in Islamic Phlosophy: Knowledge by
Presence…, 96--100. 614 Mullâ Sadrâ mengataka, tanpa pengalaman hudhuri, tidak ada yang dapat disebut
sebagai pengetahuna (yang terpercaya). Lihat, Sadra, Al-Syawâhid al-Rubûbiyyah fî al-
Manâhij al-Sulûkiyyah…, 141. 615 Nasr, Islamic Philosophy From Its Origin to the Present…, 63. 616 Kalin, Knowledge in Later Islamic Philosophy…, 256–257.
152
Dalam menerangkan argumentasi ittihad aqil wa ma'qûl, filsafat Mullâ Sadrâ
sebagaimana dijelaskan Fazlur Rahman mengajukan beberapa argumentasi. Bahwa
ilmu adalah hadirnya objek kepada subjek sehingga yang hadir kepada subjek adalah
esensi objek sehingga subjek dan objek harus identik sehingga terdapat kemungkinan
hadirnya objek kepada subjek. Pengetahuan itu bersifat immaterial sehingga subjek
dan objek haruslah sama-sama immaterial. Pengetahuan subjek kepada objek berada
dalam diri subjek617.
Untuk terjadi pengetahuan, tidak boleh sama sekali ada pemisahan antara
subjek dan objek karena menuntut adanya perantara antara subjek dan objek. Bila
perantara (penghubung) itu ada, tentu yang diketahui adalah perantaranya, demikian
seterusnya sehingga antara subjek dan objek harus merupakan bentangan kesatuan.
Hal ini dalam filsafat Mullâ Sadrâ menjadi mungkin karena adanya prinsip gerak
substansi, wujûd mental (dhihnî) kesederhanaan (bâsîth) wujûd618.
Akal manusia memiliki keunikan untuk memahami realitas tunggal hingga
mencapai hudhûrî yang menjadikan kesatuan subjek dan objek. Hal tersebut karena
jiwa manusia bergerak dalam berbagai tahapan dari ekspresi keunikan melalui
kemampuan memisahkan aksiden dan substansi, kemampuan abstraksi, kemampuan
imajinasi (seperti membayangkan pegasus dan unicorn), hingga mencapai alam
mitsal atau alam barzakh yang merupakan tingkatan gambar tetap yang sudah terlepas
dari sifat jasmani619.
Berbeda dengan ilmu hushûlî yang diperoleh melalui indra dan inteleksi, ilmu
hudhûrî diperoleh melalui hati. Hanya hati yang selalu memiliki kecenderungan
kepada kebaikan, jauh dari hawa nafsu, yang dapat mengalami ilmu hudhûrî, Dengan
pengetahuan hudhûrî, manusia melihat dengan penglihatan Haqq Ta’âlâ. Inilah yang
disebut musyahadah620. Metode perolehan ilmu menuju musyahadah adalah pertama
thabi'ah, yakni bawaan. Kedua adalah an-nafs, yaitu kecenderungan. Ketiga adalah
akal, yakni abstraksi mental, baik itu material (hayulanî), potensial (isti'dadî),
maupun aktual (fa'al). Keempat adalah ruh, yaitu sesuatu yang halus dan suci. Kelima
sirr, yaitu kondisi fânâ. Keenam khafî, yaitu fânâ dengan sifat dan perbuatan (fânâ fî
al-zat). Ketujuh khafâ, yaitu bersatu dengan Ahadiyah yang merupakan puncak
ma'rifah621.
C. Konsep Penting dalam Filsafat Mullâ Sadrâ
Terdapat beberapa konsep penting dari ajaran Mullâ Sadrâ, yakni
kemendasaran wujûd (ashalat al-wujûd), gradasi wujûd (tâskîk al-wujûd), kefakiran
akibat dalam kausalitas (illiyah), hakikat sederhana (basith al-haqîqah), gerak
617 Fazlur Rahman, The Philosophy of Mulla Sadra (Sadr Al-Din Al-Shirazi),
Knowledge Creation Diffusion Utilization, 1975, 14–15. 618 Mullâ Sadrâ, Al-Hikmah Al-Muta’âliyah Fî Al-Asfâr Al-‘Aqliyyah Al-Arba’Ah Vol.
I (Beirut: Dar Iḥyâʽ at-Turâts al-‘Arabiy, 2002), 12–13. 619 Izutsu, Sufism and Taoism: A Comparative Study of Key Philosophical Concepts…,
159. 620 Zakaria, “Dakwah Sufistik Hamzah Fansûrî: Kajian Substantif Terhadap Syair
Perahu.” 621 Nasution, “Hikmah Muta’alliyah: Analisa Terhadap Proses Sintesa Filosofis Mulla
Sadra,” 191–192.
153
substansi (al-harakah al-jawhayiah), dan kesatuan subjek dan objek (ittihad aqil wa
ma’qûl). Tiap-tiap konsep ini akan diuraikan secara rinci guna memahami gagasan
filsafat Mullâ Sadrâ. Tiap-tiap konsep ini berkesinambungan satu sama lain.
Semuanya bergantung pada gagasan utamanya, yakni kemendasaran wujûd (ashalat
al-wujûd). Semua konsep filsafat yang dicetuskan Mullâ Sadrâ merupakan sebuah
keunikan dalam filsafat karena konsep-konsep itu lahir dari respons atas konsep-
konsep filsafat, tasawuf filosofis, dan berbagai varian pemikiran sebelumnya.
7. Kemendasaran Wujûd (Ashalat al-Wujûd)
Dalam sistem ajarannya, Mullâ Sadrâ hanya menerima satu wujûd murni.
Sementara selainnya, yakni mâhiyâh, adalah sesuatu yang tidak pernah mencium
aroma wujûd. Maksudnya adalah mâhiyâh atau esensi setiap entitas itu benar-benar
bukan wujûd. Dalam makna wujûd sebagai univokal, selain wujûd adalah
ketiadaan622. Dalam filsafat Mullâ Sadrâ, status mâhiyâh adalah menghasilkan
keberagaman dari wujûd yang tunggal623. Segala konsep ajaran Mullâ Sadrâ, seperti
tâskîk al-wujûd, illiyah, ittihad aqil wa ma’qûl, kesatuan sebab dan akibat, dan bâsîth
al-haqîqâh kullî al-asyâ' berlandaskan pada konsep kemendasaran wujûd. Filsafat
Mullâ Sadrâ memandang wujûd sebagai sesuatu yang tunggal, mendasari segala
realitas. Khususnya konsep basith basit al-haqîqah (hakikat sederhana) dan illiyah
(kefakiran akibat dalam kausalitas), sangat dekat dengan Wujudiah. Prinsip ontologi
lainnya dari Filsafat Mullâ Sadrâ adalah tâskîk al-wujûd (gradasi eksistensi).
Pemahaman tentang kemendasaran wujûd muncul dari suatu pandangan
rasional yang bersifat ilahiah atau disebut Mullâ Sadrâ sebagai burhan nûr al-‘arsyî
atau secara umum disebut dengan ilmu hudhûrî. Skema ini dijelaskan oleh Mullâ
Sadrâ melalui sistem basiht al-haqîqâh kullî al-asya’624. Ketika Haqq Ta’âlâ tidak
teridentifikasi arah, tetapi Dia adalah hakikat sederhana segala sesuatu maka Dia
menjadi dasar realitas625. Keseluruhan realitas adalah kehadiran-Nya. Sementara
segala kemajemukan yang terjangkau ilmu hushûlî adalah cara kerja indra dan intelek
untuk memahami wujûd yang mendasar dan sederhana itu626.
Melalui sistem hushûlî, filsafat Mullâ Sadrâ dapat membantu menyelesaikan
masalah ini dengan mengandalkan ma’qulat tsanî falsafî. Realitas eksternal
sebagaimana klaim filsafat Mullâ Sadrâ, sebagai realitas yang memiliki wujûd maka
setiap ekstensinya adalah kandungan wujûd dan mâhiyâh627. Namun, wujûd yang
terkandung dalam satu ekstensi tidak dapat dipahami secara langsung melalui
ma’qulat awal. Karena itu, perlu dianalisis melalui ma’qulat tsanî falsafî yang
622 Dalam menjelaskan filsafat Mullâ Sadrâ, Thabattaba’i mengatakan bahwa mâhiyah
bukan wujûud, bukan pula ketiadaan mutlak. Lihat, Thabâthabâ’î, Nihayah Al-Ḥikmah…, 91–
93. 623 Sadrâ, Mullâ, Al-Hikmah Al-Muta’âliyah Fî Al-Asfâr Al-‘Aqliyyah Al-Arba’Ah Vol.
I…, 7. 624 Sadrâ, Mullâ, Al-Hikmah Muta‟aliyyah Fî Al-Ashfâr Al’Aqliyyah Al-Arba’ah, Vol.
1…, 17–18. 625 Thabâthabâ’î, Bidâyah Al-Ḥikmah…, 16. 626 Mullâ Sadrâ, Al-Hikmah Muta‟aliyyah Fî Al-Ashfâr Al’Aqliyyah Al-Arba’ah, Vol.
1…, 16–17. 627 Nasr, “Existence (Wujūd) and Quiddity (Māhiyyah) in Islamic Philosophy.”…, 409
154
merupakan sebuah sistem inteleksi yang mana diskursus ranah mental yang memiliki
acuan pada realitas628.
Melalui identifikasi suatu ekstensi sebagai mawjûd yang terbagi menjadi
keberadaan (wujûd) dan kesesuatuannya (mâhiyâh), ditemukanlah bahwa wujûd-nya
yang mendasar, sementara mâhiyâh hanyalah limitasi bagi wujûd. Dengan
menganalisis wujûd sebagai wujûd maka wujûd yang menjadi wilayah analisis itu
menjadi konsep wujûd (wujûd dhihnî)629. Menurut Mullâ Hâdî Sabzawârî630 dan
Sayyid Hussîn Thabattâbâ'i631 yang merupakan pengikut ajaran Mullâ Sadrâ, bila
konsep wujûd telah dipahami dengan baik, realitas wujûd secara otomatis terbukti
dengan sendirinya632. Untuk itu, yang perlu untuk diperjelas adalah konsep wujûd
untuk menunjukkan bagaimana wujûd itu bersifat sederhana dan tidak berlaku arah
atau tempat baginya633.
Mullâ Sadrâ mengatakan, setiap pembahasan tentang wujûd sebenarnya adalah
wujûd dhihnî meskipun dikatakan bahwa ini adalah wujûd kharijî’. Karena sesuatu
apa pun yang masuk wilayah pembahasan konseptual atau apa pun yang dapat
dikonseptualisasikan, ia adalah diskursus dalam ranah mental634. Meskipun demikian,
terkait dengan konsep wujûd maka diskursus tentang wujûd dhihnî dapat dianggap
sebagai acuan wujûd kharijî karena pikiran dapat menjadi cermin bagi realitas635.
Wujûd dhihnî adalah pembukti keberadaan wujûd kharijî yang menjadi dasar
bagi realitas. Dasar realitas adalah wujûd dibuktikan dengan efek yang muncul dari
mawjûd adalah dari wujûd-nya, bukan mâhiyâh-nya. Sebagai konsep, wujûd menjadi
628 Daniel Zuchron, Menggugat Manusia Dalam Konstitusi, (Jakarta: Rayyana
Komunikasindo, 2017),74–75. 629 Rahman, The Philosophy of Mulla Sadra (Sadr Al-Din Al-Shirazi)…, 215. 630 Toshihoko Isutzu juga membahas persoalan tersebut. Lihat, Izutsu, Struktur
Metafisika Sabzawari…, 50–55. 631 Diskursus tersebut dapat ditemukan dalam, Thabâthabâ’î, Bidâyah Al-Ḥikmah…,
22. 632 Zuchron, Menggugat Manusia Dalam Konstitusi…, 59–60. 633 Mullâ Sadrâ, Al-Hikmah Muta‟aliyyah Fî Al-Ashfâr Al’Aqliyyah Al-Arba’ah, Vol.
1…, 16–17. 634 Dengan syarat, dalam pembahasannya, terlebih dahulu membedakan dengan jelas
mana pembahasan wujûd dhhnî dan mana pembahasan wujûd kharijî. Kekeliruan atau
kesilapan membedakan suatu pembahasan wujûd, apakah dia wujûd dhhnî atau wujûd kharijî
berakibat fatal. Persis seperti yang dilakukan Syihab al-Dîn al-Suhrawardî dalam menanggapi
ontologi Ibn Sînâ . Namun kasus tersebut bukan murni kesalahan Syihab al-Dîn al-
Suhrawardî. Karena Ibn Sînâ sendiri tidak membuat pemisahan yang tegas tentang
pembagian pembahasan wujûd (wujûd dhhnî dan wujûd kharijî) dalam kegiatan filsafatnya.
Nasr al-Din Thusî-lah yang mula-mula memberikan penjelasan mana pembahasan wujûd
dhhnî dan mana pembahasan wujûd kharijî dalam filsafat Ibn Sînâ. Kontribusi Nasr al-Din
Thusî membuat kegiatan filsafat Mullâ Sadrâ menjadi lebih mudah. Pembahasan wujûd dhhnî
dalam filsafat Mullâ Sadrâ, lihat, Rahman, The Philosophy of Mulla Sadra (Sadr Al-Din Al-
Shirazi)…, 215. 635 Kholid Al-Walid mengatakan, dalam filsafat Mullâ Sadrâ, keniscayaan wujud
mental tidak dapat ditolak karena dapat menyeret kepada paham sofis. Lihat, Kholid Al-
Walid, Perjalanan Jiwa Menuju Akhirat: Filsafat Eskatologi Mulla Sadra (Jakarta: Sadra
Press, 2012), 44.
155
pemersatu segala mâhiyâh. Pada proposisi “Kursi itu ada”, “Batu itu ada”, “Kambing
itu ada”, unsur pemersatunya adalah “ada” atau wujûd. Meskipun pada ranah dhihnî
yang mendasar adalah mâhiyâh, dengan wujûd dhihnî menjadi pemersatu bagi
mâhiyâh maka dengan pandangan wujûd dhihnî adalah cermin bagi wujûd kharijî
maka pada realitas, yang mendasar adalah wujûd, sementara mâhiyâh hanyalah hal
yang mampu ditangkap persepsi dan inteleksi636. Untuk mengenal wujûd pada realitas
eksternal, kecuali dengan penjelasan konseptual, perlu melalui ilmu hudhûrî.
Dalam prinsip ajaran Mullâ Sadrâ, pada realitas eksternal yang terindrai adalah
satu entitas tunggal yang tidak rangkap. Ketika dianalisis mental maka menjadi
rangkap antara wujûd yang mengacu pada keberadaannya dan mâhiyâh yang
mengacu pada ke-apa-annya. Dalam ranah mental, mâhiyâh menjadi mendasar,
sementara wujûd atau ke-ada-annya hanya menjadi predikat bagi mâhiyâh. Misalnya,
pada setiap premis “manusia ada”, “meja ada”, “pohon ada”, dan selalu “ada” hanya
menjadi predikat bagi setiap mâhiyâh637.
Secara konseptual, wujûd itu selalu menjadi tambahan bagi mâhiyâh. Namun
pada realitas, wujûd itu menjadi dasar bagi realitas. Wujûd tidak dapat didefinisikan
karena definisi itu meniscayakan adanya genus dan differensia. Sementara wujûd
bukanlah genus dan bukan differensia. Meski tidak dapat didefinisikan, wujûd itu
tunggal mendasari realitas.
Mengenai status kemendasaran realitas wujûd, Mullâ Sadrâ638 menulis:
الشيآء بأن "ان حقيقة كل شىء هو وجود الذى يترت ب به عليه آثآره وأحكآمه. فآلوجود اذن أحق
يكونذأهقيقة، اذغير به يصيرذاهقيقة، فهو حقيقه كل ذى حقيقه، ول يحتآج هو فى آن يكون ذآ حقيقه
عيآن ل بنفسهآز" به فى األ -أعنى المآهيآت -الى حقيقه اخرى. فهو بنفسه فى األعيآن، وغيره
Terjemahannya:
“Sesungguhnya hakikat segala sesuatu adalah wujûd, yang memberikan efek
(pada realitas) dan membuatnya tampak. Jadi, wujûd adalah dasar bagi segala
sesuatu yang merupakan (satu-satunya) pemilik hakikat. Sementara segala
sesuatu memperoleh hakikat (karena wujûd). Maka dia (wujûd), (adalah)
hakikat segala sesuatu (yang memiliki hakikat). Dan dia (wujûd) tidak
membutuhkan apa pun (untuk eksis), malah yang lain itulah yang
membutuhkan kepadanya untuk eksis. Maka dia (wujûd) eksis dengan
sendirinya pada realitas. Entitas lainnya (yang disebut dengan mâhiyâh)
apabila ditemukan pada realitas pasti bersama wujûd, mustahil eksis dengan
sendirinya.
Dengan demikian, setiap entitas pada realitas eksternal, seperti “manusia itu
ada”, “kursi itu ada”, “kuda itu ada”, dan sebagainya meniscayakan adanya suatu hal
tunggal yang menyatukan semua mâhiyâh itu. Dalam hal ini, yang menyatukan
adalah wujûd karena wujûd tidak bergantung pada apa pun, sementara setiap mâhiyâh
636 Izutsu, Struktur Metafisika Sabzawari…, 68. 637 Nasr, Islamic Philosophy From Its Origin to the Present…, 67–68. 638 Sadrâ, Mullâ, Al-Masya’ir…, 10.
156
itu adalah pembatasan-pembatasan. Mâhiyâh hanya menjadikan segala entitas
memperoleh identitas spesifiknya. Mâhiyâh bukan sebagai pengada setiap entitas.
Sementara setiap entitas pada realitas itu diketahui ada, eksis. Pemberi eksistensi atau
yang membuat setiap entitas itu ada adalah wujûd. Sebagaimana dijelaskan Mullâ
Sadrâ di atas, setiap entitas mâhiyâh tidak pernah eksis dengan sendirinya pada
realitas. Setiap mâhiyâh pasti eksis bersama wujûd. Bahkan, wujûd itulah yang
membuatnya mengada. Dengan demikian, wujûd menjadi dasar bagi realitas dan
memberikan efek.
Pembuktian lainnya oleh Mullâ Sadrâ dalam al-Masya'ir’639 tentang
kemendasaran wujûd pada realitas eksternal adalah bahwa yang memberikan efek
dari realitas eksternal adalah wujûd. Sementara mâhiyâh hanyalah proyeksi mental
yang tidak memiliki acuan pada realitas. Lawan dari keberadaan adalah ketiadaan.
Mullâ Sadrâ sendiri yang menyatakan bahwa makna kemendasaran wujûd adalah
bahwa wujûd tidak membutuhkan perantara apa pun untuk mengada dan
keberadaannya adalah dengan sendirinya640. Ketika mengakui wujûd sebagai sesuatu
yang eksis dengan sendirinya maka tentunya wujûd telah mengada melampaui waktu
dan bersifat tetap. Penjelasan-penjelasan ini menunjukkan bahwa filsafat Mullâ Sadrâ
dibangun dengan basis kemendasaran wujûd yang tunggal. Konsep tersebut
merupakan landasan untuk menjelaskan berbagai konsep ajaran lainnya, seperti tâskîk
al-wujûd, illiyah, basit al-haqîqah, dan ittihad aqil wa ma’qûl.
8. Gradasi Wujûd (Tâskîk al-Wujûd)
Konsep tâskîk al-wujûd atau gradasi wujûd dalam filsafat Mullâ Sadrâ hanya
dapat dipahami dan diterima dengan syarat telah memahami dan menerima prinsip
kemendasaran wujûd (ashalat al-wujûd) yang menjadi bagian penting dari filsafat
Mullâ Sadrâ641. Kemendasaran wujûd adalah meyakini bahwa pada realitas eksternal,
yang mendasar adalah wujûd. Sementara mâhiyâh hanya eksis dalam ranah mental
sebagai pembatas wujûd agar intelek dapat mengenalinya. Wujûd yang menjadi satu-
satunya yang nyata pada realitas eksternal hanya dapat dikenali melalui mâhiyâh642.
Dalam tâskîk al-wujûd, kesatuan mengisi keseluruhan kemajemukan, kemajemukan
mengalir dalam kesatuan, kemajemukan kembali dalam kesatuan. Frasa
“kemajemukan mengalir dalam kesatuan” mengindikasikan bahwa sebenarnya
kemajemukan itu adalah penampakan kesatuan dalam modus-modus ekstensi.
Dengan memahami atau menerima prinsip kemendasaran wujûd maka tâskîk
al-wujûd menjadi dapat dipahami atau diterima. Tâskîk al-wujûd adalah jalan yang
ditempuh Mullâ Sadrâ untuk menjelaskan hubungan antara ketunggalan dan
keberagaman. Dalam sistem tâskîk al-wujûd, kemajemukan itu diterima berada dalam
wujûd yang satu. Aspek persamaannya adalah aspek perbedaan643. Analogi aspek
kesamaan adalah perbedaan adalah seperti cahaya. Cahaya seratus derajat dan cahaya
639 Sadrâ, Mullâ, Al-Masya’ir…, 12. 640 Jabir, Wahdah Al-Wujûd Ibn ‘Arabî Dan Filsafat Wujûd Mulla Sadrâ…, 65. 641 Sadrâ, Mullâ, Al-Masya’ir…, 3. 642 Nasr, Islamic Philosophy From Its Origin to the Present…, 67–68. 643 Mâ bî al-isytarak ’ain mâ bihi al-ikhtiâf. Jabir, Wahdah Al-Wujûd Ibn ‘Arabî dan
Filsafat Wujûd Mulla Sadrâ…, 69.
157
sepuluh derajat, kesamaannya adalah pada cahaya. Perbedaannya juga pada cahaya
itu sendiri. Perbedaannya adalah pada intensitas. Intensitas yang berbeda (menjadi
majemuk) itu adalah pada kesamaannya, yakni cahaya. Dalam sistem tâskîk al-wujûd,
satu entitas memiliki acuan yang berbeda. Misalnya, perbedaan pada sisi
kualitasnya644.
Dalam sistem tâskîk al-wujûd, tidak ada padanya perbedaan secara totalitas
karena bila berbeda total, tidak ada keragaman atau kesatuan padanya. Tidak pula
dalam tâskîk al-wujûd yang benar-benar tunggal. Bila demikian, keberagaman tidak
akan ada. Dalam tasykîk, ketunggalan dan sekaligus kemajemukan itu ada. Tâskîk
hanya ada dalam wujûd, sementara pada mâhiyâh tidak karena antar mâhiyâh sama
sekali tidak ada aspek kesamaan. Syarat-syarat dalam tasykîk al-wujûd adalah
kesatuan wujûd itu riil, kemajemukan wujûd itu riil, kemajemukan kembali kepada
kesatuan, dan kesatuan mengalir dalam kemajemukan645.
Kesan yang dapat ditangkap dalam hal ini adalah pengakuan bahwa
kemajemukan itu sebenarnya kembali kepada ketunggalan dan kesatuan itu mengalir
dalam kemajemukan sehingga sebenarnya kemajemukan itu tidak benar-benar lepas
dari ketunggalan. Kemajemukan senantiasa berada dalam ketunggalan. Ketunggalan
selalu nyata dalam kemajemukan646. Maka dari itu, mengesankan bahwa yang benar-
benar nyata adalah ketunggalan. Kemajemukan memang riil, tetapi di dalam
ketunggalan. Oleh sebab itu, apabila diberikan pertanyaan, “Bagaimana status
kemajemukan?” Maka jawabannya adalah, “Kemajemukan itu adalah ketunggalan.”
Kemajemukan harus riil. Bila tidak, gradasi tidak dapat berlaku. Sekaligus
kesatuan juga harus riil. Bila tidak, tidak ada penghubung kemajemukan.
Kemajemukan mengalir dalam ketunggalan. Juga kemajemukan kembali kepada
ketunggalan. Karena itu, semua kemajemukan itu sebenarnya berlandaskan pada satu
hakikat, yakni ketunggalan. Kemajemukan itu hanya pada kualitas647. Karena kualitas
itu berada pada level aksiden, sejatinya kemajemukan itu hanya suatu aksiden. Dan
aksiden adalah proyeksi mental, tidak memiliki realitas hakiki. Akan tetapi,
penyimpulan ini tidak diterima sebagian pengikut Mullâ Sadrâ, seperti Muhammad
Taqî Misbâh Yazdî. Sadrian sepertinya mengeklaim bahwa kemajemukan itu harus
benar-benar eksis karena bila tidak, tidak ada yang bisa disebut sebagai kesatuan.
Sebagian pengkaji Mullâ Sadrâ lainnya berpandangan, setiap entitas yang
berbeda-beda yang ditemukan pada realitas eksternal bukanlah perbedaan total. Ada
aspek kesamaan dalam perbedaan-perbedaan itu sehingga membuat wujûd dari setiap
keberagaman itu dapat diabstraksikan. Abstraksi juga hanya dapat dilakukan apabila
terdapat keberagaman. Karena itu, terdapat satu entitas tunggal yang mendasari
keberagaman. Perbedaan antarentitas yang beragam adalah dalam satu wujûd tunggal
yang bergradasi648.
Dalam sistem tâskîk al-wujûd, dibuktikannya bahwa gradasi itu memang riil
pada realitas eksternal adalah dengan adanya wujûd yang lebih dahulu, seperti wujûd
644 Rahman, The Philosophy of Mulla Sadra (Sadr Al-Din Al-Shirazi…), 35. 645 Izutsu, Struktur Metafisika Sabzawari…, 38. 646 Jabir, Wahdah Al-Wujûd Ibn ‘Arabî Dan Filsafat Wujûd Mulla Sadrâ…, 27. 647 Jabir, Wahdah Al-Wujûd Ibn ‘Arabî Dan Filsafat Wujûd Mulla Sadrâ…, 73. 648 Rahman, The Philosophy of Mulla Sadra (Sadr Al-Din Al-Shirazi)…, 35.
158
akal dan ada wujûd yang lebih kemudian seperti wujûd imajinal. Ada pula wujûd yang
lebih kuat, seperti wujûd sebab dan ada pula wujûd yang lebih lemah, seperti wujûd
akibat. Pandangan tersebut sebenarnya berbeda dengan pandangan Wujudiah dan
tentunya tidak memiliki kesamaan dengan pemikiran filsafat sebelumnya. Namun,
Mullâ Sadrâ mengeklaim bahwa gagasan tâskîk al-wujûd itu tidak bertentangan
dengan pandangan sufi Wujudiah. Mullâ Sadrâ649 menjelaskan:
و مما يجب أن يعلم أن إثباتنا لمراتب الوجودات المتكثرة و مواضعتنا في مراتب البحث و التعليم على
تعددها و
ينافي ما نحن بصدده من ذي قبل إن شاء هللا من إثبات وحدة الوجود و الموجود ذاتا و حقيقة تكثرها ل
كما هو مذهب األولياء و العرفاء من عظماء أهل الكشف و اليقين
Artinya:
“Perlu dipahami bahwa pembuktian kami terhadap tingkatan-tingkatan
wujûd yang berbeda-beda dan meletakkannya pada dasar dalam tingkatan-
tingkatan pembahasan dan pengajaran atas keragamannya dan
kemajemukannya (wujûd), tidak bertentangan dengan apa yang akan kami
buktikan pada pembahasan selanjutnya (insya’ Allah) tentang pembuktian
bahwa wujûd dan mawjûd secara esensi dan secara hakikat adalah sebagaimana
yang diyakini para aulia dan ‘urafâ’ yang mana mereka semua adalah orang-
orang yang telah memperoleh pengingkapan batin dan telah memperoleh
pengetahuan hakiki”
Namun, sepertinya Mullâ Sadrâ dalam pernyataan di atas ingin menegaskan
bahwa gagasan tâskîk al-wujûd adalah sebuah sintesis dari pemikiran-pemikiran
sebelumnya. Diskursus ini berakar dari pemikiran Ibn Sînâ. Karena menerima
mumkin al-wujûd bergantung secara mutlak kepada Wajib al-Wujûd, seharusnya Ibn
Sînâ menerima kesatuan wujûd. Akan tetapi sebaliknya, malah menerima
keberagaman wujûd para realitas eksternal. Padahal, makna kebergantungan mutlak
mumkin al-wujûd atas Wajib al-Wujûd bȋ nafsihȋ sehingga mumkin al-wujûd menjadi
wajȋb al-wujud bȋ ghayrihȋ, menunjukkan wajȋb al-wujud bȋ ghayrihȋ yang majemuk
itu sebenarnya adalah satu kesatuan sekaligus kemajemukan dalam status gradasi
(taskik). Fazlur Rahman selaku pengkaji serius pemikiran Ibn Sînâ mengatakan
bahwa Ibn Sînâ menerima dualitas wujûd dan mâhiyâh para realitas eksternal. Oleh
sebab itu, Fazlur Rahman mengkritik Mullâ Sadrâ dengan mengatakan bahwa Mullâ
Sadrâ tidak tepat mengandalkan pemikiran Ibn Sînâ untuk mengkritik pendapat
Syihab al-Dîn al-Suhrawardî untuk menegaskan bahwa yang nyata pada realitas
adalah wujûd, bukan mâhiyâh. Sebenarnya, Mullâ Sadrâ sudah tepat menggunakan
argumentasi Ibn Sînâ untuk menegaskan pandangan bahwa yang nyata pada realitas
eksternal adalah wujûd. Karena sebenarnya Ibn Sînâ, sebagaimana dijelaskan Nasr
al-Dîn Thûsî, bermaksud mengatakan bahwa sebenarnya dualitas wujûd dan mâhiyâh
(dalam pandangan Ibn Sînâ) adalah pada ranah mental, bukan pada realitas eksternal.
Dalam hal ini, Fazlur Rahman mengikuti penafsiran Ibn Rusyd terhadap pemikiran
649 Mullâ Sadrâ, Al-Hikmah Muta’aliyyah Fî Al-Asfâr Al-’Aqliyyah Al-Arba’ah Vol.
1, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-’Arabi, 2002), 92.
159
Ibn Sînâ. Pandangan Ibn Rusyd dan Fazlur Rahman meyakini bahwa dualitas wujûd
dan mâhiyâh pada realitas eksternal tampaknya ingin membuat konsistensi dengan
pandangan kemajemukan wujûd pada realitas eksternal yang dipegang Ibn Sînâ.
Sebab itulah, meskipun pada beberapa bagian pembahasan lain Fazlur Rahman
mengakui bahwa Mullâ Sadrâ mengambil penafsiran Nasr al-Dîn Thûsî, pada bagian
ini tidak. Karena itu, sebenarnya Mullâ Sadrâ menerima gagasan Ibn Sînâ
sebagaimana ditafsikan Nasr al-Dîn Thûsî bahwa perbedaan wujûd dan mâhiyâh
adalah pada ranah mental. Namun sayangnya, Ibn Sînâ malah menerima gagasan
bahwa wujûd itu nyata pada realitas eksternal, tetapi majemuk berdasarkan perbedaan
mâhiyâh. Padahal, mâhiyâh itu adalah proyeksi mental. Mullâ Sadrâ juga menerima
kemajemukan, tetapi memahami kemajemukan itu berdasarkan kemajemukan
mâhiyâh pada ranah mental maka sebenarnya gagasan Mullâ Sadrâ sangat dekat
dengan Wujudiah sekaligus telah meluruskan kesimpulan Ibn Sînâ. Dalam perspektif
lain, dapat ditafsirkan bahwa Mullâ Sadrâ menerima kemajemukan wujûd riil pada
realitas eksternal sebagai konsekuensi atas akomodasinya atas sistem filsafat. Sebab
itulah, gagasan tâskîk al-wujûd dimaknai beragam oleh para pengkaji Mullâ Sadrâ.
Dalam hal ini, dapat diduga bahwa gagasan tâskîk al-wujûd ingin menyintesis ajaran
Ibn Sînâ dan Ibn ‘Arabî, sekaligus ajaran Syihab al-Dîn al-Suhrawardî.
Gagasan tâskîk itu sendiri dirumuskan dari semangat manifestasi cahaya
Syihab al-Dîn al-Suhrawardî. Sementara itu, meski sebenarnya dapat diketahui
bahwa kaum sufi Wujudiah tidak menjelaskan tentang gagasan gradasi (tâskîk),
namun sebagaimana pernyataan di atas, Mullâ Sadrâ mengeklaim gagasan tersebut
sejalan dengan sufi Wujudiah. Klaim tersebut melahirkan pandangan dari kelompok
Sadrian untuk menegaskan bahwa ajaran Mullâ Sadrâ memang sangat cocok
dimaknai sebagai sebuah ajaran tasawuf filosofis sebagaimana Ibn ‘Arabî dan
lainnya. Akan tetapi, sebagian Sadrian lainnya tidak dapat menerima pandangan
demikian karena dengan jelas mereka dapat menemukan bahwa konsep tâskîk al-
wujûd itu berbeda dengan ajaran Wujudiah. Perdebatan tersebut masih berlangsung
hingga hari ini.
9. Kefakiran Akibat dalam Kausalitas (Illîyah)
Bagian penting lainnya yang membuat ajaran filsafat Mullâ Sadrâ menjadi unik
adalah konsep tentang kefakiran akibat dalam kausalitas (Illiyah). Kausalitas adalah
untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya hubungan antara sebab dan akibat.
Kausalitas merupakan bagian penting dalam aliran filsafat dan kâlâm. Mutakallimîn
menilai bahwa keniscayaan bergantungnya akibat pada sebab adalah pada sisi
kebaruannya. Sementara Mullâ Sadrâ berpandangan, keniscayaan bergantungnya
akibat kepada sebab adalah karena status wujûd akibat yang bergantung (mumkîn,
contigent) pada wujûd sebab. Selama mengada, wujûd akibat selalu bergantung pada
wujûd sebab650.
Dalam pandangan kâlâm, wujûd akibat itu independen dari wujûd sebab.
Wujûd akibat itu sifatnya baru, sementara wujûd sebab itu tetap. Maka dari itu,
keduanya dianggap berbeda. Dalam pandangan mutakallimîn, sebab dan akibat itu
650 Riahi, “A Study Of The Effect Of Human Soul On External Objects : Between
Copenhagen School And Mulla Sadra,” 19.
160
memiliki wujûd yang berbeda. Wujûd sebab lain, wujûd akibat lain651. Demikian juga
dalam al-Hikmah al-Masyâ'iyyah maka wujûd sebab lain, wujûd akibat lain. Segala
entitas pada realitas eksternal memiliki wujûd masing-masing yang berbeda. Padahal
seharusnya, akibat dalam pandangan al-Hikmah al-Masyâ'iyyah, persis seperti sebab
karena al-Hikmah al-Masyâ'iyyah menerima bahwa akibat adalah mumkîn. Sebagai
mukmin al-wujûd, akibat bergantung secara mutlak kepada Wajîb al-Wujûd bî
Nafsîhî652. Kebergantungan akibat pada sebab sebagai kebergantungan mumkîn pada
wajîb persis kebergantungan kopula pada subjek. Kopula benar-benar tidak memiliki
eksistensi. Kopula benar-benar tunduk kepada subjek. Demikian seharusnya
kebergantungan akibat sebagai mumkîn kepada sebagai sebab sebagai wajîb sesuai
dengan pandangan filsafat Mullâ Sadrâ653.
Dengan menerima mumkîn al-wujûd sebagai akibat, sekalipun telah menjadi
wajîb al-wujûd bî ghayrîhî, tetap saja adalah akibat dari Wajîb al-Wujûd bî Nafsîhî.
Sementara al-Hikmah al-Masyâ'iyyah berpandangan bahwa pada setiap wajîb al-
wujûd bî ghayrîhî berbeda dengan wajîb al-wujûd bî ghayrîhî lainnya karena
perbedaan setiap mâhiyâh-nya. Karena itu, sudah seharusnya setiap wajîb al-wujûd
bî ghayrîhî sebagai akibat bergantung pada Wujûd Tunggal, yakni Wajîb al-Wujûd bî
Nafsîhî yang menjadi sebabnya. Akan tetapi, pengakuan demikian tidak ada dalam
al-Hikmah al-Masyâ'iyyah. Sebab itulah, Mullâ Sadrâ terkesan semacam meluruskan
al-Hikmah al-Masyâ'iyyah 654. Alasan lainnya al-Hikmah al-Masyâ'iyyah
berpandangan wujud sebab dan wujud akibat berbeda adalah karena konsekuensi
pandangannya yang membedakan wujûd pada realitas eksternal menurut tiap-tiap
mâhiyâh-nya.
Dalam usaha menyempurnakan filsafat, Mullâ Sadrâ melihat akibat sebagai
sesuatu yang bergantung secara mutlak kepada sebab. Sebenarnya, pandangan ini
terinspirasi dari gagasan al-Hikmah al-Masyâ'iyyah tentang status mumkîn al-wujûd
sebagai akibat yang mutlak bergantung kepada wajîb al-wujûd sebagai sebab. Akan
tetapi, mumkîn al-wujûd hanya cocok untuk sistem kemendasaran mâhiyâh. Karena
sebenarnya dalam kemendasaran wujûd, yang riil seharusnya hanyalah wujûd.
Sementara selainnya adalah realitas konseptual. Maka dari itu, akibat harus
dipandang sebagai sesuatu yang tidak memiliki eksistensi, kecuali eksistensinya
adalah kehadiran sebab. Akibat sejatinya tidak memiliki zat sehingga akibat bukan
tambahan bagi zat akibat karena sejatinya zat akibat adalah akibat itu sendiri ('ain al-
rabith bî al-illah). Hal ini karena akibat itu adalah kefakiran mutlak655. Sistem filsafat
Mullâ Sadrâ melihat akibat sebagai kefakiran. Akibat bergantung mutlak kepada
sebab sehingga dinamai rabith illî. Karena dalam sistem kausalitas yang berbasis
kemendasaran wujûd, wujûd hanya dapat dibagi kepada wujûd mandiri yang
651 Perbedaan signifikan pandangan teolog dan ’urafa, lihat, Nasution, “Termination
OF Wahdah al-Wujûd In Islamic Civilization In Aceh: Critical Analysis of Ithaf Ad-Dhaki,
The Works of Ibrahim Kurani,”…, 401. 652 Rahman, The Philosophy of Mulla Sadra (Sadr Al-Din Al-Shirazi)…, 33–34. 653 Kartanegara, Gerbang Kearifan: Sebuah Pengantar Filsafat Islam…, 82–83. 654 Rahman, The Philosophy of Mulla Sadra (Sadr Al-Din Al-Shirazi)…, 63–64. 655 Jabir, Wahdah Al-Wujûd Ibn ‘Arabî dan Filsafat Wujûd Mulla Sadrâ…, 74–76.
161
dipandang sebagai sebab (mustaqil) dan wujûd yang bergantung secara mutlak
kepada wujûd sebab (rabith)656.
Wujûd akibat dalam sistem proposisi dipandang sebagai kopula sebagai
penghubung antara subjek dan predikat. Misalnya, dalam proposisi "Ahmad adalah
penulis", suatu kopula sama sekali tidak memiliki independensi. Kata “adalah”
benar-benar bergantung (rabith), tidak memiliki independensi. Yang memiliki
independensi (mustaqil) hanya “Ahmad” dan “penulis” karena dapat dipahami secara
mandiri. Suatu kopula hanya berfungsi sebagai penghubung bagi subjek dan predikat.
Kata “Ahmad” dan kata “penulis” dapat ditemukan acuannya di realitas eksternal.
Sementara kopula tidak memiliki acuan pada realitas ekstenal. Kopula hanya
berfungsi untuk menunjukkan keterangan subjek yang riil pada realitas eksternal.
Karena itu, status kopula sebagai penjelasan bagi status akibat dalam sistem
kausalitas, hanya memiliki nama, tetapi tidak memiliki wujûd.
Dalam sistem kausalitas, Mullâ Sadrâ menegaskan bahwa sebenarnya akibat
itu bukan suatu hakikat yang berdiri sendiri. Akibat adalah sesuatu yang tidak bisa
dilepaskan dari akibat. Dalam hal ini, Mullâ Sadrâ657 menulis:
” ء و المعلول بما هو معلول ل يعقل إل مضافا إلى العلة فانفسخ ما أصلناه من الضابط في كون الشي
العتبار سوى كونه مضافا و لحقا و ل علة و معلول هذا خلف فإذن المعلول بالذات ل حقيقة له بهذا
معنى له غير كونه أثرا و تابعا من دون ذات تكون معروضة لهذه المعاني كما أن العلة المفيضة على
اإلطلق إنما كونها أصل و مبدأ و مصمودا إليه و ملحوقا به و متبوعا هو عين ذاته"
Terjemahannya:
“Akibat sebagaimana dianya akibat sama sekali tidak memiliki hakikat kecuali
dihubungkan dengan sebab. Dan hal ini tidak berarti kecuali akibat adalah efek
sebab dan mengikuti sebab. Tanpa memiliki zat sebagai lokus aksiden dari
makna-makna tersebut. Sebagaimana sebab yang memberikan emanasi secara
mutlak, bahwa sesungguhnya makna dari inti, sumber, yang memenuhi
kebutuhan yang lain, yang diikuti adalah hakikat zat sebab pemberi emanasi
itu sendiri.
Dalam hal ini, Mullâ Sadrâ ingin menjelaskan bahwa sejatinya akibat itu sama
sekali tidak memiliki eksistensi. Akibat itu adalah kefakiran mutlak. Hakikat akibat
tidak lain kecuali kefakirannya atas sebab. Hakikat akibat hanyalah keakibatan itu
sendiri. Dalam hal ini, hakikat hanya dimiliki oleh wujûd sebab (mustaqîl). Sementara
status akibat itu seperti kopula (râbith). Kopula itu sendiri dianggap hanya eksis
dalam ranah mental.
Namun, ada yang mirip dengan wujûd rabith pada realitas eksternal, yaitu
wujûd aksiden. Seperti “putih” sebagai wujûd aksiden yang pada realitas eksternal
hanya bisa eksis dengan menjadi sifat bagi wujûd lainnya, seperti putih pada realitas
eksternal yang hanya bisa eksis sebagai aksiden bagi tembok. Akan tetapi, wujûd
aksiden memiliki eksistensi untuk dirinya sekalipun dirinya itu menjadi sifat bagi
yang lain, seperti putih yang menjadi sifat bagi tembok. Sementara kopula untuk
656 Jabir, Wahdah Al-Wujûd Ibn ‘Arabî dan Filsafat Wujûd Mulla Sadrâ…, 74. 657 Mullâ Sadrâ, Al-Hikmah Muta’aliyyah Fî Al-Asfâr Al-’Aqliyyah Al-Arba’ah Vol.
2, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-’Arabi, 2002), 244.
162
dirinya saja tidak memiliki eksistensi. Eksistensi kopula adalah kebergantungan itu
sendiri658. Demikian status setiap ekstensi (mawjûdat) sama sekali tidak memiliki
eksistensi (wujûd). Eksistensinya adalah kebergantungan itu sendiri.
Dalam sistem kopula kausal Mullâ Sadrâ, hakikat akibat adalah keakibatan itu
sendiri. Bila tidak, sebab menjadi tambahan bagi hakikat akibat sehingga akibat tidak
membutuhkan sebab. Hal ini mustahil. Karena pada kenyataannya, akibat bergantung
secara mutlak kepada sebab. Hakikat akibat adalah kebutuhan dan kefakiran mutlak.
Tidak ada apa pun pada diri akibat, kecuali kebergantungan itu sendiri kepada
sebab. Dalam sistem kopula kausal, pada realitas eksternal, hanya ada satu wujûd
yang menjadi dasar realitas. Namun, dalam analisis mental terdapat tiga entitas, yakni
sebab yang memberikan wujûd, akibat sebagai yang memberikan wujûd, dan aktivitas
pemberian wujûd659.
10. Hakikat Sederhana (Basith al-Haqîqah)
Konsep basith al-haqîqah (hakikat sederhana) adalah segala sesuatu dan tidak
ada ada apa pun darinya (منها وليسا بشعين آسيا كل ي الحقيقة sebenarnya merupakan ,(بسث
pintu masuk fondasi dan prinsip dasar seluruh bangunan al-Hikmah al-Muta’alliyah.
Mullâ Sadrâ menjelaskan pandangan tersebut secara panjang lebar dalam
karyanya660. Sebenarnya, prinsip inilah yang menghantarkan kaidah-kaidah lain
dalam konsep-konsep filsafat Mullâ Sadrâ, termasuk kemendasaran wujûd (aslât al-
wujûd) yang merupakan salah satu fondasi penting ajarannya661. Melalui prinsip
basit al-haqîqah (hakikat sederhana), Mullâ Sadrâ tidak hanya hendak menyelesaikan
banyak persoalan filsafat yang diwariskan oleh para filosof masa lalu, tetapi juga
melalui fondasi ini, Mullâ Sadrâ ingin menyelesaikan persoalan aliran pemikiran
lainnya, seperti kâlâm, khususnya mengenai keesaan Tuhan dan mengenai hubungan
antara Dzat dan Sifat Tuhan662.
Konsep basith al-haqîqah adalah sebuah terobosan baru dalam filsafat Islam.
Syihab al-Dîn al-Suhrawardî telah menunjukkan kegagalan definisi sebagai prasyarat
proposisi dalam filsafat. Lalu, dia menegaskan bahwa hanya dengan ilmu hudhûrî
saja pengetahuan sejati dapat diperoleh663. Menerima pandangan Syihab al-Dîn al-
Suhrawardî ini, Mullâ Sadrâ melakukan revolusi filsafat dari sistem definisi menuju
sistem presentasi (hudhûrî) sebagai prasyarat proposisi. Mullâ Sadrâ mengaku
konsep hakikat sederhana yang dia perkenalkan adalah hasil kontemplasi dan
658 Mullâ Sadrâ, Al-Hikmah Al-Muta’âliyah Fî Al-Asfâr Al-‘Aqliyyah Al-Arba’Ah Vol.
I, 319. 659 Hal ini mempertemukan konsep kesatuan subjek dan objek dalam filsafat Mulla
sadra dan kesatuan yang mengetahui, yang diketahui dan pengetahuan dalam tasawuf Hamzah
Fansûrî. Al-Walid, Tasawuf Mulla Shadra: Konsep Ittihad Al-’Aqil Wa Al-Ma’qul Dalam
Epistemologi Filsafat Dan Makrifat Ilahiyyah, 127; Al-Attas, The Mysticism of Hamzah
Fansûrî…, 274. 660 Mullâ Sadrâ, Al-Hikmah Al-Muta’âliyah Fî Al-Asfâr Al-‘Aqliyyah Al-Arba’Ah Vol.
I…, 12–13. 661 Mullâ Sadrâ, Al-Masya’ir…, 3. 662 Mullâ Sadrâ, Al-Hikmah Al-Muta’âliyah Fî Al-Asfâr Al-‘Aqliyyah Al-Arba’Ah Vol.
I…, 16–17. 663 Suhrawardi, “Hikmah Al-Isyrâq,”…, 11-`16.
163
perenungan mendalam sehingga terbukalah baginya hijab. Maka dengan itu, Mullâ
Sadrâ meraih pengetahuan presentasi. Dalam berbagai biografi tentang riwayat hidup
Mullâ Sadrâ, disebutkan bahwa dia melakukan kontemplasi selama lima belas tahun
hingga memperoleh pengetahuan presentasi. Hasil pengetahuan ini menjadi dasar
Mullâ Sadrâ menulis filsafatnya dalam Asfar dan beberapa buku lainnya, seperti
Hikmah Arsyiyah', 'al-Masya'ir, dan sebagainya664.
Pengalaman presentasi (hudhûrî) itu disebut Mullâ Sadrâ sebagai hikmah
'arsyiyah malakûtî Ilahî. Karena itu, kegiatan filsafat Mullâ Sadrâ dapat dikatakan
sebagai sebuah filsafat tertinggi dengan alasan bahwa dia menjadikan pengetahuan
yang bersifat pasti, terang, dan meyakinkan, yaitu ilmu presentasi sebagai elemen
mendasar kegiatan filsafatnya. Oleh Mullâ Sadrâ, pengetahuan ini disebut sebagai
burhan 'arsyî665 karena pembuktian filsafat yang dia lakukan adalah menjustifikasi
pengetahuan tertinggi atau al-hikmah al-ilahiyah melalui argumentasi filsafat. Sistem
ini membuat filsafat Mullâ Sadrâ memiliki basis argumentasi yang solid. Sistem
demikian perlu diambil semangatnya dalam pengembangan filsafat dan ilmu
pengetahuan.
Konsep basit al-haqîqah hanya dapat diperoleh melalui ‘ilmû ladunnî666. Dasar
pengetahuan yang diperoleh melalui cara demikian atau disebut dengan ilmu hudhûrî
dianggap oleh Mullâ Sadrâ dan para pengikutnya sebagai prasyarat bagi filsafat yang
berkualitas. Sependapat dengan penekanan Syihab al-Dîn al-Suhrawardî bahwa filsuf
sejati adalah mereka yang memperoleh dasar pengetahuan melalui ilmu presentasi
sekaligus mampu mengemukakan pengetahuannya itu dengan argumentasi filsafat
yang sistematis dan solid, diakui sebagian filosof pengikut Mullâ Sadrâ tidak akan
sempurna melakukan kegiatan berfilsafat sebelum memperoleh burhân ‘arsyî atau
kasyaf. Berdasarkan pengalaman presentasi, Mullâ Sadrâ melakukan kegiatan
berfilsafat yang sistematis melalui argumentasi-argumentasi yang solid667.
Makna basith dalam konsep basit al-haqîqah adalah berarti mutlak, tidak
rangkap atau tidak komposit dengan apa pun. Kesederhanaannya tidak terdiri atas
berbagai rangkap, baik itu rangkap materi dan bentuk, rangkap genus dan differensia,
rangkap wujûd dan mâhiyâh, maupun rangkap wujdin (ada) dan fiqdan (tiada). Basit
al-haqîqah bebas dari berbagai jenis rangkapan. Ia sederhana, tidak rangkap.
Melampaui genus dan differensia yang disebut Wujûd Mutlak668. Dalam Wujudiah,
disebut Wujûd Haqq Ta’ala669.
Dalam hal ini, Mullâ Sadrâ670 menegaskan:
664 Rahman, The Philosophy of Mulla Sadra (Sadr Al-Din Al-Shirazi)…, 2–3. 665 Mullâ Sadrâ, Al-Hikmah Al-Muta’âliyah Fî Al-Asfâr Al-‘Aqliyyah Al-Arba’Ah Vol.
I…, 135. 666 Mullâ Sadrâ mengatakan pengetahuan tersebut diperoleh melalui “hikmah 'arsyiyah
malakuti Ilahi” yang disebut dengan ’burhan ‘arsyi’. Sadrâ, Mullâ,, Al-Hikmah Al-
Muta’âliyah Fî Al-Asfâr Al-‘Aqliyyah Al-Arba’Ah Vol. I…, 135. 667 Miswari, Filsafat Terakhir…, 178–178. 668 Dalam filsafat Islam, Wujud mutlak melampaui genus dan differensia telah
dikemukakan sejak Al-Kindi. Lihat, Al-Kindi, On First Philosophy, (Harvard: Harvard
University Press, 1974), 14. 669 Nasr, “Introduction to Mystical Tradition,”…, 367. 670 Sadrâ, Mullâ, al-Masya’ir…, 8-9.
164
" كما -شمول حقيقة الوجود لألشياء الموجودة ليس كشمول معنى الكلي للجزئيات، و صدقه عليهامن أن حقيقة الوجود ليست جنسا و ل نوعا و ل عرضا إذ ليست كليا. طبيعيا، بل شموله -نبهناك عليه
”ضرب آخر من الشمول
Terjemahannya:
Kemencakupan hakikat wujûd atas segala mawjudat, bukan seperti
kemencakupan universalia atas partikularitas, dan (bukan pula sepeti
kemencakupan) predikasi universal atas partikular-partikularnya. Dari karena
hakikat wujûd bukan genus, dan bukan spesies, dan bukan pula seperti kulî tabi’i
(universal natural). Tetapi kemencakupan (hakikat wujûd) berbeda dengan
kemencakupan-kemencakupan (universalia itu).
Sebagaimana dijelaskan Mullâ Sadrâ di atas, wujûd yang sederhana dan
mencakup segala sesuatu, tetapi bukan segala sesuatu itu. Kemencakupan wujûd
bukan sebagaimana kemencakupan universalia atas partikular dan bukan pula seperti
kemencakupan genus atas spesies. Dalam hal ini, wujûd juga tidak dapat didefinisikan
karena segala hal yang dapat didefinisikan adalah hal-hal yang memiliki genus dan
differesia. Sementara wujûd tidak memiliki genus dan differensia.
Pada realitas eksternal terdapat wujûd yang menjadi acuan basit al-haqîqah
sebagai suatu kesederhanaan mutlak. Sebagai kesederhanaan mutlak, eksistensinya
memiliki kesempurnaan segala sesuatu. Sebagai kesempurnaan segala sesuatu, basit
al-haqîqah memiliki kesempurnaan segala sesuatu, bukan menjadi segala sesuatu671
sehingga basit al-haqîqah itu menjadi segala sesuatu. Hal ini karena segala sesuatu
itu kesempurnaannya adalah pada wujûd. Maka dari itu, basit al-haqîqah al-haqîqah
adalah wujûd segala sesuatu, tetapi bukan segala sesuatu karena segala sesuatu itu
adalah komposisi wujûd dan mâhiyâh. Wujûd adalah realitas segala sesuatu,
sementara mâhiyâh adalah proyeksi mental.
Meskipun diakui inspirasi konsep hakikat sederhana adalah dari pengalaman
hudhûrî, Mullâ Sadrâ, sebagaimana konsep-konsep lainnya, seperti ashalat al-wujûd,
tâskîk al-wujûd, illiyah, dan lainnya mempertahankan argumentasinya, antara lain,
dengan pendekatan filsafat672. Argumentasi basit al-haqîqah setidaknya dibangun
melalui tiga premis. Pertama, berdasarkan ashalat al-wujûd dan tâskîk al-wujûd.
Rangkaian kausalitas dimulai dari puncak piramida wujûd hingga wujûd paling
bawah, yakni wujûd alam materi. Kedua, sebagaimana dalam pembahasan kausalitas,
sebab hakiki adalah yang memberikan wujûd atau kesempurnaan kepada akibat
sehingga tentunya sebab memiliki kesempurnaan karena sesuai dengan kaidah filsafat
yang tidak memiliki mustahil dapat memberikan. Karena itu, wujûd sebab atau basit
al-haqîqah pasti memiliki kesempurnaan yang terdapat pada tingkatan wujûd
setelahnya. Ketiga, dalam skema piramida wujûd, berbagai mawjûdat yang ada pada
tingkatan bawah memiliki rangkap, baik itu rangkap dengan mâhiyâh maupun
rangkap dengan sempurna dan kurang sempurna. Yang paling sempurna adalah
hakikat sederhana karena tidak memiliki rangkap. Berdasarkan tiga premis
argumentasi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesederhanaan hakiki pada
671 Jabir, Wahdah Al-Wujûd Ibn ‘Arabî Dan Filsafat Wujûd Mulla Sadrâ…, 79. 672 Murtadha Mutahhari, Filsafat Hikmah…, 77–78.
165
basit al-haqîqah karena tidak memiliki rangkap sehingga segala sesuatu (al-asya')
hakikatnya berada dalam hakikat sederhana (basith al-haqiqî). Segala sesuatu adalah
pancaran hakikat sederhana. Pada segala sesuatu adalah kehadiran basit al-haqîqah.
Skema ini sama dengan tâskîk al-wujûd yang terkandung dalam satu wujûd673.
Meskipun hanya menerima satu wujûd yang dinisbahkan kepada Haqq Ta’ala
yang tunggal, Wujudiah dan filsafat Mullâ Sadrâ tidak sama dengan nihilisme yang
menolak eksistensi realitas eksternal. Dua ajaran tersebut tidak menolak realitas
eksternal selain Haqq Ta’ala. Wujudiah berpandangan bahwa selain Haqq Ta’ala
adalah manifestasi (tajallî) atau penampakan (zuhûr) Haqq Ta’ala yang terjadi pada
Nama-nama Haqq Ta’ala. Sementara filsafat Mullâ Sadrâ berpandangan bahwa
wujûd itu tunggal sekaligus bergradasi.
11. Gerak Substansi (al-Harakah al-Jawhayiah)
Gerak substansi (al-harakah al-jawhayiah) adalah revolusi yang dilakukan
Mullâ Sadrâ dalam sistem pemikiran filsafat filsafat. Sebelumnya, para filosof
menerima prinsip ajaran Aristotelian yang menegaskan gerak hanya terjadi pada level
aksiden. Bagi Mullâ Sadrâ, perubahan aksiden adalah karena substansinya yang
bergerak. Gerak substansi yang dirumuskan Mullâ Sadrâ ini dipengaruhi gerak cinta,
khususnya ajaran dalam Wujudiah Ibn ‘Arabî. Dengan gerak substansi maka
perubahan satu entitas wujûd menjadi entitas wujûd lainnya menjadi keniscayaan.
Pandangan ini sejalan dengan prinsip tasykîk al-wujûd yang dirumuskan Mullâ Sadrâ
sendiri.
Setidaknya terdapat tiga argumen yang dinisbahkan kepada dalil Mullâ Sadrâ
dalam membuktikan gerak substansi. (1) Premis pertama: (a) perubahan aksiden
adalah akibat alami dari perubahan substansi. Agen terdekat dari gerak mustahil di
luar materi. Karena itu, pasti dari materi itu sendiri. Ini berarti dari substansinya.
Premis kedua: (b) sebab gerak pasti bergerak. Bila sebab terdekatnya tetap, padahal
perantara antara subjek dan objek tidak ada maka pastinya objeknya tetap juga.
Misalnya, cahaya lampu yang bergerak mengindikasikan lampu yang bergerak. (2)
Premis pertama: (a) aksiden tidak terpisah dengan substansi, bahkan aksiden adalah
pancaran substansi: (b) setiap perubahan yang terjadi pada pancaran (aksiden) adalah
indikasi perubahan pada sumbernya (substansi). Kesimpulannya: gerak aksiden
adalah bukti gerak substansi. Argumen kedua ini dibangun berdasarkan pancaran
sebagaimana pancaran cahaya, suatu pendekatan yang lebih senyawa, dibandingkan
argumen pertama yang melalui kausal yang mungkin dianggap parsial. (3) Mullâ
Sadrâ menyatakan waktu adalah dimensi keempat dari karakteristik materi. Karena
itu, mewaktu adalah keniscayaan bagi materi. Keniscayaan ini tentunya terjadi pada
substansi. Konsekuensinya, setiap materi pasti bergerak secara terus-menerus674.
Gerak adalah kesempurnaan pertama pada sesuatu yang bersifat potensi
ditinjau dari keberadaannya sebagai potensi (kamal al-awwal li ma bi al-quwwah min
haitsu inna hu bi al-quwwah). Makna dari “kesempurnaan pertama” (kamal al-
awwal) aktualitas sesuatu sebagai substansi sebagai lokus aksiden untuk ikut
mengaktual. Makna “potensi ditinjau dari keberadaannya sebagai potensi” (min
673 Jabir, Wahdah Al-Wujûd Ibn ‘Arabî Dan Filsafat Wujûd Mulla Sadrâ…, 80–81. 674 Thabâthabâ’î, Nihayah Al-Ḥikmah…, 208-210.
166
haitsu innahu bȋ al-quwwah) adalah sempurnanya aktualitas potensi pertama
sekaligus sempurnanya potensialitas bagi aktualisasi potensi baru yang menjadi
aktualitas potensi pertama. Sebab itulah, gerak juga didefinisikan sebagai ‘keluarnya
sesuatu dari potensi menuju aktualitas secara gradual’ (khuruju al-syai‟i min al-
quwwah ila al-fi‟il tadrijan). Gerak merupakan kesempurnaan (kamal), namun
kesempurnaan pada dalam gerak berbeda dengan kesempurnaan pada yang lain.
Kesempurnaan pada gerak adalah ketika kesempurnaan pertama yang di dalamnya
terdapat potensi yang sempurna sebagai persiapan aktualisasi selanjutnya. Gerak
merupakan proses pembaharuan terus menerus wujûd suatu entitas. Gerak merupakan
perjalanan terus-menerus sebagai suatu proses munculnya suatu mawjûdat dari
potensialitas menuju aktualitas.
Gerak pada aksiden terjadi pada empat kategori aksiden, yaitu kualitas (al-
kaif), kuantitas (al-kam), tempat (al-ain), dan posisi (al-wadh‟). Keberadaan gerak
pada empat kategori ini diakui oleh umumnya filosof sebelum Mullâ Sadrâ. Adapun
Mullâ Sadrâ melihat gerak yang terjadi pada empat kategori aksiden itu terjadi karena
akibat adanya gerak pada substansinya. Mullâ Sadrâ675 menjelaskan:
"إذا جاز في الكم والكيف وأنواعهما كون أنواع بالنهاية بين طرفيها بالقوة مع كون الوجود المتجدد
,’أمر أشخصيا من باب الكم أو الكي فليجز مثل ذلك في الجوهر الصوري؛ فيمكن اشتداده واستكماله
اته بحيث يكون وجود واحد شخصى مستمر متفاوت الحصول في شخصيته ووحدته الجوهرية".في ذ
Terjemahannya:
“Bila terjadi (gerak) pada kuantitas dan kualitas dan bagian-bagiannya yang
tak terbatas antara keduanya terjadi secara potensial, dalam arti bahwa wujûd
itu selalu baharu dalam identitasnya, baik pada kuantitas ataupun kualitas.
Maka hal tersebut dapat juga terjadi pada ranah substansi. Sehingga
memungkinkan terjadinya penguatan dan penyempurnaan pada zat-nya
sebagai wujud dengan identitas yang satu secara terus-menerus, berbeda
dalam sampainya identitas dan kesatuan substansial”
Bagi Mullâ Sadrâ, relasi aksiden dan substansi adalah satu realitas. Ini adalah
konsekuensi dari prinsip kesatuan wujûd. Aksiden adalah kondisi-kondisi substansi
bukan tegaknya dua entitas. Mullâ Sadrâ mengistilahkan relasi antara substansi dan
aksiden adalah relasi illuminatif (idhafah isyraqiyah). Gerak pada substansi
merupakan sumber semua gerak dalam kategori aksidennya, yakni kuantitas, kualitas,
posisi, dan tempat. Penyebab gerak itu adalah wujûd yang satu.
Dalam gerak terdapat enam unsur, yakni penggerak (muharrik), yang
digerakkan (mutaharrik), titik awal (mabda’), titik akhir (muntaha atau ghayah),
aspek yang bergerak (mâ fîhî al-ḥarakah), dan waktu (zaman). Mullâ Sadrâ
menjelaskan bahwa penggerak adalah wujûd. Titik awal adalah wujûd bî al-kuwwah
(potensi). Titik akhir adalah wujûd wujûd bî al-al-fi’il (aktual). Aspek yang bergerak
adalah modus kehadiran penggerak (muharrik) berupa substansi dan empat aksiden
yang terlibat gerak. Waktu adalah abstraksi mental terhadap wujûd yang bergerak.
675 Mullâ Sadrâ, Al-Hikmah Muta‟aliyyah fî Al-Ashfâr Al’Aqliyyah Al-Arba’ah, Vol.
3, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-’Arabi, 2002), 69.
167
Pandangan kesatuan antara substansi dan aksiden yang meniscayakan konsep
gerak substansi dalam filsafat Mullâ Sadrâ tidak dapat dimungkiri adalah penegasan
bagi konsep kesatuan wujud sebagaimana diakui pemikir Wujudiah. Mullâ Sadrâ
mencoba menjelaskan kesatuan wujûd dalam bentuk kesatuan wujûd yang bergradasi
(taskîk). Mullâ Sadrâ mengajarkan wujûd adalah satu, namun bergradasi (tasykîk).
Sistem tasykîk diinspirasikan dari ajaran Syihab al-Dîn al-Suhrawardî tentang
illuminasi cahaya. Perbedaan dalam satu wujûd adalah pada kedahuluan-
kebelakangan atau kesempurnaan-kekurangsempurnaan676
Dalam ajaran Mullâ Sadrâ, wujûd itu sederhana sekaligus meliputi segala
sesuatu. Wujûd itu mengisi keseluruhan realitas, tetapi setiap entitasnya bukan wujûd.
Secara teori kefilsafatan dalam diskursus tentang kategorisasi wujûd, Mullâ Sadrâ
menerima prinsip pembagian wujûd Ibn Sînâ. Mullâ Sadrâ menerima kategorisasi
wujûd, yakni Wâjib al-Wujûd lî nafsihî, wâjib al-wujûd lî ghayrihî, mumkîn al-wujûd,
dan mumtanî’ al-wujûd. Perbedaan dari Ibn Sînâ adalah Mullâ Sadrâ tidak menerima
pembagian entitas wujud bagi setiap mawjûdat pada realitas eksternal (kharijî).
Kemendasaran wujûd yang dimaksud Ibn Sînâ dan Mullâ Sadrâ berbeda. Bagi Ibn
Sînâ, wujûd memang mendasar pada realitas, tetapi tiap-tiap wujûd itu berbeda
menurut perbedaan mâhiyah-nya. Sementara bagi Mullâ Sadrâ, wujûd itu mendasar
pada realitas eksternal dan sekaligus tunggal mencakupi segala sesuatu. Mullâ Sadrâ
sepakat dengan Ibn Sînâ dalam pembedaan wujûd dengan mâhiyah pada ranah
konseptual. Ketika masuk ke ranah konseptual, wujûd hanya sebagai predikat yang
tidak mendasar dan mâhiyah menjadi subjek yang mendasar. Maka dari itu, wujûd
hanya menjadi tambahan bagi mâhiyah dalam ranah mental. Sementara pada realitas
eksternal, wujûd-lah yang mendasar.677
Gagasan ontologi Mullâ Sadrâ sangat dekat dengan Wujudiah Ibn ‘Arabî.
Prinsip kesatuan wujûd merupakan ajaran ‘irfân. Sementara Mullâ Sadrâ ikut
berdialog secara intens dengan filsafat maka dia tidak dapat menerima wahdat al-
wujûd, kecuali ditempatkan dalam sistem tasykîk al-wujûd dan basîth haqîqat kulli
asyya’ (wujûd sebagai entitas sederhana, tetapi meliputi segala sesuatu). Gagasan
kesatuan dan kemendasaran wujûd ini berkonsekuensi kepada pemahaman Mullâ
Sadrâ tentang gerak sehingga merumuskan konsep gerak substansi. Gerak substansi
adalah pergerakan menuju kesempurnaan. Pada dirinya sebagai aktualitas, wujûd
jasmani sekaligus adalah potensialitas. Potensialitas ini menjadi aktual ketika jiwa
terlepas dari jasad. Jiwa yang telah terlepas dari jasad adalah aktualitas murni.678
Karena gerak substansi merupakan proses menuju kesempurnaan, mustahil terjadi
gerak terbalik. Sesuatu yang dari lebih sempurna menjadi kurang sempurna adalah
mustahil. Gerak menuju kesempurnaan itu dinamis dan aktualitas sejati adalah setelah
jiwa melepaskan diri dari jasad maka bagi Mullâ Sadrâ reinkarnasi itu mustahil.
676 Muḫammad Nur Jabir, Wahdah Al-Wujûd Ibn ‘Arabî dan Filsafat Wujûd Mulla
Sadrâ..,71. 677 Seyyed Hossein Nasr, “Existence (Wujūd) and Quiddity (Māhiyyah) in Islamic
Philosophy,” International Philosophical Quarterly 29, no. 4 (1989), 409–428. 678 Kerwanto, “Manusia Dan Kesempurnaannya (Telaah Psikologi Transendental
Mullā Shadrā),”…, 133.
168
Sistem filsafat yang dibangun Mullâ Sadrâ dapat menjelaskan pengalaman
spiritual berdasarkan argumentasi rasional. Dapat dikatakan bahwa apa yang
dilakukan Mullâ Sadrâ merupakan suatu terobosan dalam pemikiran Islam. Mullâ
Sadrâ meyakini gerak tidak hanya pada tataran aksiden, tetapi juga substansi. Gerak
jiwa misalnya, diketahui secara hudhûrî, seperti bertambah atau berkurangnya rasa
cinta atau rasa benci. Pergerakan aksiden sebenarnya adalah tanda bagi gerak
substansi.
12. Kesatuan Subjek dan Objek (Ittihad Aqil wa Ma’qûl)
Dalam filsafat Mullâ Sadrâ, pengetahuan adalah menyatunya subjek dan objek.
Penyatuan Konsep ini juga merupakan bagian dari gagasan kesatuan dan
kemendasaran wujûd. Prinsip sistem pengetahuan ini adalah penerimaan atas ilmu
presentasi (hudhûrî) yang sebenarnya merupakan sistem tasawuf filosofis. Mullâ
Sadrâ mengembangkan sistem tersebut dalam sistem filsafat. Sebab itulah, filsafatnya
tidak dapat dilepaskan dari ajaran Wujudiah.
Dalam sistem epistemologi yang dirumuskan Mullâ Sadrâ, pengetahuan
representasi terbagi menjadi konsepsi (tasawwur) dan afirmasi (tasydiq). Sebuah
proposisi bisa hanya sebatas konsepsi, bisa pula disertai afirmasi. Konsepsi adalah
sebuah penerimaan atas suatu pernyataan tanpa penilaian, misalnya penilaian apakah
pernyataan itu benar atau diterima atau pernyataan itu tidak benar atau tidak
diterima679. Dalam pengetahuan representasi, berdasarkan keragaman acuan (referen
atau rujukan atau acuan), terbagi menjadi universal (kullî), yaitu acuan plural, seperti
“manusia”, “kota”, dan acuan tunggal, seperti “Sukarno”, “Jakarta”680. Di samping
itu, epistemologi filsafat Mullâ Sadrâ juga menerima pembagian pengetahuan dalam
bentuk pengetahuan aksiomatis (badîhî) dan pengetahuan teoretis (nazharî).
Pengetahuan aksiomatis adalah pengetahuan yang diperoleh tanpa melalui inferensi
atau deduksi. Sementara pengetahuan teoretis adalah pengetahuan yang diperoleh
melalui inferensi atau deduksi681.
Dalam pemikirannya, Mullâ Sadrâ berpendapat bahwa pengetahuan empiris
menjadi awal pengetahuan. Akan tetapi, rasio juga berperan penting dalam
menentukan atau mengonstruksi pengetahuan melalui fakultas jiwa yang
mencakup indra (hiss), fantasi (khayalî), estimasi (wahmî), dan inteleksi (buhanî).
Selain mengakomodasi realis sekaligus empiris, filsafat Mullâ Sadrâ juga dapat
679 Konsepsi masih berupa gambar yang dari ke dalam mental. Tetapi afirmasi telah
terkandung justifikasi [baik afirmasi maupun negasi]. Mustahil ada afirmasi tanpa didahului
afirmasi. Miswari, Filsafat Pertama…, 23. 680 Konsep terbagi menjadi [1] konsep universal dan [2] konsep partikular. Konsep
universal terbagi menjadi [1] konsep universal gradasional dan [2] konsep universal univokal.
Konsep partikular terbagi menjadi: [1] Konsep partikular hakiki, yaitu tidak ada lagi partikular
di bawahnya, contoh: Jakarta, Soekarno. [2] Konsep partikular relatif, yaitu yang menjadi
partikular ketika dibandingkan dengan konsep lebih luas darinya, contoh: konsep ‘manusia’
jika dibandingkan konsep ‘hewan’. Konsep partikular relatif menjadi konsep partikular hakiki
bila: hanya dapat diterapkan pada satu eksistensi dan menjadi partikular universal ketika:
konsepnya dapat dibagi menjadi beberapa konsep lagi. Penjelesan lengkap mengenai kaidah
ini, lihat, Miswari, Filsafat Pertama…, 23, 3. 681 Nasution, Filsafat Ilmu Pengetahuan…, 39–40.
169
dikatakan sebagai filsafat realis karena menerima pengetahuan presentasi (hudhûrî)
dan menjadikannya sebagai sistem pengetahuan yang lebih mendasar682. Sistem
epistemologi ilmu presentasi (hudhûrî) dalam filsafat Mullâ Sadrâ mengakui bahwa
hakikat realitas (ke-ada-annya) dapat diketahui melalui kehadiran subjek kepada
objek tersebut dengan kemenyatuan antara subjek dan objek atau dalam filsafat
istilahnya disebut ittihad aqil wa ma’qûl683. Sistem ini meniscayakan tiga aspek
dalam sistem pengetahuan, yaitu subjek yang mengetahui (‘aqil), objek yang
diketahui (ma’qûl), dan pengetahuan (‘aql) sebagai proses pengetahuan684. Sistem ini
mirip dengan sistem pengetahuan Tuhan dalam Wujudiah.
Pencapaian pengetahuan presentasional (hudhûrî) merupakan capaian tertinggi
filsafat Mullâ Sadrâ sehingga disebut al-hikmah al-muta'alliyah. Filsafat semacam
ini sebenarnya telah dirintis oleh Syihab al-Dîn al-Suhrawardî. Menurut Syihab al-
Dîn al-Suhrawardî, seorang filsuf yang baik adalah yang telah mencapai pengetahuan
tertinggi, namun mampu mengemukakan kesaksiannya secara rasional685. Peringatan
Syihab al-Dîn al-Suhrawardî ini dipegang dengan baik oleh Mullâ Sadrâ dan para
pengikutnya. Dalam hal ini, Muhammad Taqî Misbâh Yazdî mengatakan, bangunan
rasional filsafat seharusnya sesuai dengan ilmu presentasi sehingga filsafat dan
tasawuf sebenarnya adalah dua bidang ilmu yang integral686.
Pengetahuan menurut sistem Mullâ Sadrâ adalah kehadiran jiwa pada objek.
Jiwa adalah kesempurnaan utama dari raga alami wadah yang mengandung potensi
kehidupan687. Maksud kesempurnaan utama adalah sesuatu yang esensial yang
membentuk differensia dari satu spesies. Misalnya, pembentuk “berpikir” bagi
“hewan” sehingga menjadi “manusia”688. Raga alami maksudnya adalah raga palsu
(misalnya, patung manusia). Wadah (instrumen, 'aliy) maksudnya adalah batasan
raga yang menjadi aktualitas jiwa. Sementara "memiliki potensi kehidupan”
maksudnya memiliki potensi tumbuh, menyerap nutrisi, berkembang biak, bergerak
dengan kehendak, dan mengindrai689.
682 Al-Mandary, Menuju Kesempurnaan: Pengantar Pemikiran Mulla Sadra…, 204. 683 Kholid Al-Walid, Tasawuf Mulla Shadra: Konsep Ittihad Al-’Aqil Wa Al-Ma’qul
Dalam Epistemologi Filsafat Dan Makrifat Ilahiyyah, (Bandung: MPress, 2005), 114–115. 684 Faiz, “Eksistensialisme Mulla Sadra,” Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran
Islam (2015)…, 436. 685 Suhrawardi, “Hikmah Al-Isyrâq,”…, 11–13. 686 Taqi Miṣbâḥ Yazdî, Al-Manhaj Al-Jadîd Fî Ta’lîm Al-Falsafah Vol. 1, (Beirut: Dâr
at-Ta’ârûf lî al-Mathbu'at, 1990), 85–86. 687 Kamal awal jism thabi’i allazî hayatî bî al-quwwah, lihat, Hasan Zadeh Amuli, Al-
Ta’lîqât ‘Alâ Al-Hikmah Al-Muta’aliyah fî al-Asfâr al-'Aqliyyah al-Arba’ah, (Teheran:
Mu‟assasah al-Ŝibâ‟ah wa al-Nasyr li Wizârah al-Tsaqâfah wa al-Irsyâd al-Islâmî, 1386H),
73. 688 Terdapat pula kesempurnaan sekunder seperti menulis bagi manusia. Gama,
Filsafat Jiwa: Dialektika Filsafat Islam, dan Filsafat Barat Kontemporer…, 126 . 689 Fakultas atau daya jiwa meliputi: (1) tumbuh, (2) menyerap nutrisi, (3) berkembang
biak, (4) bergerak dengan keehendak, (5) menginderai, (6) fantasi, (7) estimasi, dan (8)
inteleksi. Dari nomor satu hingga tiga dimiliki tumbuhan. Dari nomor satu hingga tujuh
dimilihi hewan dan semuanya dimiliki manusia. Dari nomor lima hingga delapan disebut
170
Meskipun menjadi kesempurnaan utama jiwa, raga materi komposit dengan
jiwa. Misalnya, keberlangsungan jasad bergantung pada menyerap nutrisi karena
keberlangsungan raga bergantung pada materi. Kedirian seseorang bersifat utuh. Itu
karena kedirian itu adalah jiwa. Sementara raga bersifat komposit. Kehilangan bagian
tertentu dari jasad tidak menyebabkan diri seseorang menjadi tidak utuh. Sementara
keberlangsungan jiwa juga tidak bergantung pada raga. Raga hanya menjadi
instrumen persiapan bagi kehadiran jiwa690. Misalnya, seseorang pernah mengetahui
sesuatu, lalu dia lupa. Kemudian, dapat mengingat kembali tanpa membutuhkan raga
untuk mengindrainya kembali691. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan itu
bersifat immateri. Persepsi, imajinasi, estimasi, dan inteleksi itu adalah daya jiwa.
Salah satu pensyarah ajaran Mullâ Sadrâ, Jawadî Amûlî, mengatakan bahwa setiap
penentu suatu spesies adalah substansi, jiwa adalah penentu spesies maka jiwa adalah
substansi692.
Kekuatan jiwa manusia digambarkan Mullâ Sadrâ sebagai sesuatu yang sangat
mengagumkan. Selain mampu mengendalikan objek pengetahuan di alam mental,
bahkan oleh orang yang kehadiran Ilahi sangat kental padanya mampu mewujudkan
yang hadir ke dalam alam mentalnya untuk aktual di alam eksternal. Kemampuan
tersebut dapat terjadi karena manusia yang suci adalah pancaran yang baik bagi
Wujûd Ilahi.
Pengetahuan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan melalui aksiden. Karena
aksiden-aksiden itu tidak terbantahkan diterima sebagai proyeksi inteleksi, tentunya
pengetahuan itu adalah pada wujûd-nya. Jadi, pengetahuan adalah kehadiran wujûd
pada wujûd sehingga sebenarnya wujûd itu adalah sesuatu yang tunggal. Dengan
keunikan jiwa manusia yang juga merupakan bagian dari kesatuan wujûd maka daya
jiwa membentuk aksiden atas wujûd sehingga memunculkan kemajemukan. Karena
itu, sebenarnya daya jiwa manusia adalah suatu karunia yang sangat unik.
Kemampuan membuat predikasi-predikasi, termasuk membuat predikasi negatif juga
sebenarnya adalah bagian dari keagungan jiwa.
Dalam penjelasan tentang konsep Ittihad Aqil wa Ma’qûl, Mullâ Sadrâ693
menjelaskan:
فان الصورة المعقولة من الشئ المجردة عن المادة سواء كان تجردها بتجريد مجرد إياها عن المادة أم بحسب الفطرة فهي معقولة بالفعل ابدا سواء عقلها عاقل من خارج أم ال
Terjemahannya:
persepsi atau idrak. Sepertinya Mulla Sadra menerima secara utuh pandangan Ibn Sînâ
tentang tingkatan jiwa. Lihat, Miswari, Filsafat Terakhir, 205. 690 Gama, Filsafat Jiwa: Dialektika Filsafat Islam, Dan Filsafat Barat Kontemporer…,
131. 691 Sadrâ, Mullâ, Al-Hikmah Muta’aliyyah fî Al-Asfâr al-’Aqliyyah Al-Arba’ah Vol. 8
(Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-’Arabi, 2002), 225-226. 692 Amuli, Al-Ta’lîqât ‘Alâ Al-Hikmah Al-Muta’aliyah fî al-Asfâr al-'Aqliyyah al-
Arba’ah…, 207–211. 693 Mullâ Sadrâ, Al-Hikmah Muta‟aliyyah Fî Al-Ashfâr Al’Aqliyyah Al-Arba’ah,
Vol. 3…, 249.
171
“Forma-forma dalam objek akal itu bersifat abstrak (immateri), baik melalui
abstraksi dari materi oleh seorang subjek atau pun telah hadir sejak awal dalam
dirinya. Itu semua merupakan objek akal yang aktual, baik ditangkap oleh akal
seorang subjek dari realitas eksternal ataupun tidak.”
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa objek pengetahuan itu sebenarnya
bukannya sesuatu yang bersifat immaterial, melainkan kehadiran wujûd pada wujûd
melalui kreativitas jiwa. Jiwa itu sendiri merupakan bagian dari wujûd. Semua
kejadian pengetahuan atau hal-hal yang terlibat dalam pengetahuan, yakni subjek
yang mengetahui, objek yang diketahui, dan hubungan antara keduanya yang disebut
pengetahuan, semuanya terjadi dalam wujûd. Pengetahuan sejatinya adalah perluasan
jiwa. Pengetahuan merupakan bagian dari proses penyempurnaan jiwa.
Karakteristik pengetahuan hushûlî sebenarnya adalah proyeksi kreativitas jiwa
melalui fakultas tertentu dari jiwa dan sebenarnya adalah pengetahuan hudhûrî maka
apabila belum memahami bahwa kemajemukan yang merupakan proyeksi mental,
jiwa akan selalu merasa gelisah karena belum memahami bahwa sebenarnya dia
sedang menciptakan hijab bagi dirinya yang sebenarnya merupakan bagian dari
kesatuan wujûd atas objek pengetahuannya yang sebenarnya adalah juga merupakan
bagian dari kesatuan wujûd. Jiwa yang demikian selalu melahirkan waham negatif.
Sementara jiwa yang telah memahami bahwa dirinya sebagai subjek pengetahuan dan
objek pengetahuannya adalah satu kesatuan wujûd, dapat senantiasa melahirkan
pandangan positif. Meskipun demikian, jiwa dalam kategori ini menyadari bahwa
segala proyeksi atas wujûd tidak sama dengan realitas sejati wujûd. Untuk itulah,
pandangan yang harus selalu dimunculkan adalah mengakui bahwa, “Maha Suci
Engkau, tiada kukenal Diri-Mu dengan sempurna kenal”.
D. Pemaknaan Filsafat Mullâ Sadrâ
Mullâ Sadrâ mendayagunakan berbagai khazanah pemikiran Islam dalam
mengembangkan ajarannya. Dia melakukan sangat banyak kritik terhadap berbagai
varian intelektual Islam. Di samping itu, dia juga mengambil sangat banyak inspirasi
dari berbagai khazanah tersebut. Mullâ Sadrâ membangun sistem filsafatnya dengan
menyintesis berbagai varian pemikiran sehingga konsep-konsep dalam filsafatnya
harus dibangun dengan argumentasi yang luas dan mendalam. Sistem tersebut sesuai
dengan konteks keilmuan dan budaya masa Mullâ Sadrâ karena pada masa tersebut,
diskursus keilmuan berlangsung pesat dan para ilmuwan di sana sedang berlomba
melakukan sintesis berbagai varian ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, Mullâ Sadrâ
tidak perlu mengkhawatirkan komunitas pembaca karyanya meskipun dirumuskan
dalam sistem yang berat dan rumit.
Sekalipun memberi perhatian yang tinggi pada pengkajian filsafat, masyarakat
Persia selalu memiliki ekspektasi bahwa gagasan yang dikembangkan para pemikir
yang mereka miliki berorientasi pada mistisme. Hal ini dapat ditunjukkan dengan
bagaimana mereka sangat mengapresiasi karya pamungkas Ibn Sînâ al-Hikmah al-
Masyriqiyyah sekalipun sebenarnya gagasan penting Ibn Sînâ adalah corak filsafat
Aristotelian. Demikian juga mereka sangat berbangga dengan capaian Syihab al-Dîn
al-Suhrawardî yang melahirkan gagasan filsafat cahaya yang bercorak mistis dan
mengkritik gagasan utama Aristotelian. Oleh komunitas intelektual Persia, awalnya
172
gagasan Mullâ Sadrâ itu ditentang karena dianggap menghidupkan kembali sistem
Aristotelian karena Mullâ Sadrâ menerima banyak kaidah filsafat Ibn Sînâ, seperti
tingkatan fakultas jiwa, pembagian konsep wujûd, kategori substansi dan aksiden, dan
beberapa gagasan lainnya. Namun, penyelidikan yang lebih luas dan mendalam
menunjukkan bahwa filsafat Mullâ Sadrâ juga bernuansa mistis yang sangat dekat
dengan Wujudiah atau ‘irfan dalam istilah populer di Persia.
Mullâ Sadrâ telah melakukan sebuah integrasi keilmuan yang canggih dengan
melibatkan Wujudiah dan berbagai aliran filsafat sebelumnya, seperti Wujudiah, al-
Hikmah al-Isyrâqiyyah, al-Hikmah al-Masyâ'iyyah, dan lainnya untuk mengonstruksi
sebuah aliran dalam filsafat Islam, yakni al-Hikmah al-Muta’alliyah. Bagaimana
sistem integrasi antardisiplin ilmu dilakukan dalam pemikiran Islam dapat dipelajari
dari sistem sintesis Mullâ Sadrâ. Filsafat Mullâ Sadrâ sangat unik dari berbagai
dimensi. Dia mendayagunakan khazanah pemikiran sebelumnya dengan sangat
efektif. Mullâ Sadrâ menerima prinsip kemendasaran wujûd dari Ibn Sînâ, menerima
prinsip kesatuan Wujûd dari Ibn ‘Arabî, sekaligus menerima gradasi wujûd yang
diinspirasikan dari Syihab al-Dîn al-Suhrawardî. Hal yang tidak kalah penting dari
penyerapan Mullâ Sadrâ dari khazanah sebelumnya adalah penolakan validitas
definisi dan menggantikannya dengan presentasi (hudhûrî). Semangat ini juga
diambil dari Syihab al-Dîn al-Suhrawardî. Sintesis ini menjadikan filsafat Mullâ
Sadrâ menjadi sangat unik dan menjadi mirip dengan Wujudiah.
Mullâ Sadrâ melanjutkan diskursus penting dalam filsafat Islam mengenai
diskursus mana yang lebih mendasar antara wujûd dan mâhiyâh. Tugas ini awalnya
dibahas oleh Al-Farabî, dilanjutkan oleh Ibn Sînâ dan Syihab al-Dîn al-Suhrawardî.
Mullâ Sadrâ beruntung karena hidup pasca Nasr al-Dîn Thusî. Hal ini karena nama
terakhir ini telah memperjelas konteks diskursus tersebut yang sebelumnya
disalahpahami oleh Syihab al-Dîn al-Suhrawardî. Keuntungan tersebut membuat
Mullâ Sadrâ menjadi lebih mudah dalam mendiskusikan problem tersebut.
Kesimpulan Mullâ Sadrâ tentang kemendasaran wujûd semakin membuat ajarannya
secara prinsipiel makin mirip dengan iktikad Wujudiah.
Pemahaman Mullâ Sadrâ dalam epistemologi tentang keidentikan subjek dan
objek juga sangat mirip dengan sistem Wujudiah. Mullâ Sadrâ dan Wujudiah sepakat
bahwa tiga perangkat dalam pengetahuan, yakni subjek yang mengetahui, objek yang
diketahui, dan hubungan keduanya yang disebut pengetahuan adalah klasifikasi
mental atas pengetahuan yang sebenarnya adalah kehadiran Wujûd Wujûd jiwa pada
Wujûd objek pengetahuan yang mana sebenarnya keduanya adalah satu wujûd.
Pandangan tersebut berangkat dari prinsip kesatuan wujûd yang dipahami Wujudiah
dan Mullâ Sadrâ.
Kemendasaran wujûd (ashalat al-wujûd) merupakan prinsip ajaran Mullâ
Sadrâ yang menjadi landasan atas segala konsep pemikirannya. Prinsip tersebut
bukan sebatas penerimaan konseptual dalam filsafat dengan mendukung gagasan Ibn
Sînâ. Mullâ Sadrâ mengakui prinsip tersebut diperoleh melalui pengalaman spiritual
yang tinggi sebagaimana dialami para penganut Wujudiah. Prinsip kemendasaran
wujûd itu tidak benar-benar identik dengan gagasan Wujudiah karena dalam
sistemnya, Mullâ Sadrâ merumuskan konsep gradasi wujûd (tâskîk al-wujûd) yang
mana gagasan tersebut tidak dikenal dalam ajaran Wujudiah. Konsep gradasi wujûd
173
(tâskîk al-wujûd) yang dirumuskan Mullâ Sadrâ termasuk gagasan yang penuh
ambiguitas. Pada satu sisi dia menerima ketunggalan, namun keberagaman juga
diakui nyata adanya. Ketunggalan mengalir dalam keberagaman, sekaligus
keberagaman kembali kepada ketunggalan. Jadi, secara sekaligus Mullâ Sadrâ
menerima ketunggalan sekaligus menerima keberagaman sama-sama nyata694.
Berbeda dengan konsep gradasi wujûd (tâskîk al-wujûd) yang membuat ajaran
Mullâ Sadrâ menjadi berbeda dengan Wujudiah, gagasan Mullâ Sadrâ tentang
kefakiran akibat atas sebab membuat ajarannya sangat mirip dengan iktikad
Wujudiah. Pemahaman tentang hal ini mengakui bahwa makhluk itu benar-benar
tidak memiliki apa pun di hadapan Haqq Ta’ala. Jadi, Mullâ Sadrâ, sesuai dengan
Wujudiah, berpandangan bahwa jangankan apa pun, makhluk itu wujûd saja tidak
punya. Demikianlah kefakiran mutlak akibat atas sebab.
Kefakiran akibat atas sebab menunjukkan bahwa yang benar-benar nyata
hanya satu hakikat. Hakikat tunggal itu benar-benar mendasar dan mengisi realitas.
Pemahaman demikian dirumuskan dalam konsep hakikat sederhana (basith al-
haqîqah). Konsep ini adalah suatu realitas sempurna sehingga menjadi penegak bagi
setiap ekstensi (mawjûdat). Segala entitas realitas itu bukanlah apa-apa, kecuali
kehadiran wujûd secara terus-menerus. Kehadiran ini terjadi karena kesempurnaan
dari hakikat sederhana (basith al-haqîqah) yang bukan apa pun dari berbagai entitas
sekaligus menjadi segalanya bagi entitas-entitas itu. Konsep hakikat sederhana
(basith al-haqîqah) juga masih mengusung kesan ambiguitas sebagaimana konsep
gradasi wujûd (tâskîk al-wujûd).
Di antara gagasan Mullâ Sadrâ yang membuat pemikirannya sangat unik dalam
konstelasi filsafat dan membuatnya tidak dapat dilepaskan dari tasawuf filosofis,
yakni gagasan tentang gerak substansi (al-harakah al-jawhayiah). Biasanya dalam
sistem filsafat yang diterima para filosofnya adalah gerak itu merupakan perubahan
yang terjadi pada empat level aksiden, yakni kualitas, kuantitas, tempat, dan posisi.
Namun, oleh Mullâ Sadrâ gerak aksiden itu dikatakan terjadi karena adanya gerak
pada substansi. Filosof sebelumnya tidak menerima gerak pada substansi karena
substansi anggap sebagai penopang bagi aksiden yang bergerak. Gagasan gerak
substansi itu diinspirasikan oleh gagasan gerak cinta dari ajaran Wujudiah Ibn ‘Arabȋ.
694 Izutsu, Struktur Metafisika Sabzawari…, 38.
174
BAB V
ANALISIS PERBANDINGAN WUJUDIAH HAMZAH FANSÛRÎ
DAN FILSAFAT MULLÂ SADRÂ
Antara Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ memiliki banyak persamaan dan
perbedaan. Persamaan-persamaan antara dua pemikir ini adalah bagian-bagian yang
sangat prinsipiel dalam ajaran masing-masing. Hal yang menjadi alasan utama
pembentukan berbagai persamaan itu tidak lepas dari prinsip Mullâ Sadrâ yang
menerima sistem pengetahuan hudhûrî sebagai sumber pengetahuan yang valid. Di
samping itu, proses menuju pengetahuan valid itu juga ditempuh dengan cara yang
sama, yakni dengan perjalanan ke dalam diri, yakni sebuah perjalanan yang bersifat
kontemplatif dalam rangka menghidupkan daya terpenting dari jiwa, yakni
penyingkapan spiritual.
Sementara itu, perbedaan yang sangat mencolok dari pemikiran Hamzah
Fansûrî dan Mullâ Sadrâ adalah latar belakang budaya yang berbeda dari tiap-tiap
pemikir ini. Hamzah Fansûrî hidup dan menyebarkan ajarannya di tanah Melayu yang
mana masyarakatnya tidak menghidupkan sistem filsafat Aristotelian, namun
mengenal sistem pemikiran Wujudiah. Sementara Mullâ Sadrâ hidup dalam konteks
masyarakat ilmiah Persia yang mengenal baik sistem filsafat Aristotelian di samping
ajaran Wujudiah yang dikenal dengan istilah ‘irfan. Corak lingkungan ilmiah Persia
itu membuat Mullâ Sadrâ banyak mendiskusikan sistem pemikiran Aristotelian dalam
bentuk kritik pada bagian tertentu dan dukungan pada bagian lainnya. Konsekuensi
dari latar belakang inilah yang membuat Mullâ Sadrâ berbeda dengan Hamzah
Fansûrî dalam penerimaannya pada keabsahan kemajemukan. Sementara Hamzah
Fansûrî sebagai pengajar Wujudiah tidak dapat menerima bahwa kemajemukan itu
benar-benar eksis pada realitas eksternal. Bagi Hamzah Fansûrî, wujûd sebagai
hakikat realitas adalah satu dan mutlak, tidak ada kemajemukan, kecuali hanya
konstruksi mental (wahmî). Sementara Mullâ Sadrâ menerima ketunggalan sekaligus
kemajemukan wujûd sebagai hal yang riil pada realitas eksternal.
A. Persamaan Wujudiah Hamzah Fansûrî dan Filsafat Mullâ Sadrâ
Antara Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ memiliki banyak kesamaan dalam
prinsip ajaran. Beberapa persamaan yang dapat ditunjukkan dengan jelas sesuai
dengan potret analisis dari tiap-tiap pemikir, yakni pertama, persamaan dalam
pemahaman kesatuan dan kemendasaran wujûd. Keduanya berpandangan bahwa
wujûd adalah entitas mendasar yang menjadi pembentuk realitas. Kedua, Hamzah
Fansûrî dan Mullâ Sadrâ mengakui bahwa pengenalan diri sebagai awal menuju
pengetahuan sejati. Persamaan kedua ini berkonsekuensi pada kesamaan mereka pada
bagian kesamaan lainnya, yakni, ketiga, pengakuan bahwa ilmu hudhûrî sebagai
pengetahuan sejati.
Di samping itu, terdapat persamaan keempat, yaitu Hamzah Fansûrî dan
Mullâ Sadrâ juga sama-sama mengakui bahwa alam potensial itu nyata adanya.
Mereka mengakui bahwa pluralitas di alam itu semuanya berpangkal pada suatu alam
175
potensial yang telah eksis dalam Ilmu Tuhan. Dalam hal ini, keduanya menggunakan
istilah yang berbeda695 dan sepakat bahwa alam potensial itu nyata. Kelima, Hamzah
Fansûrî dan Mullâ Sadrâ juga sepakat bahwa makhluk itu semuanya bergantung
secara mutlak kepada Haqq Ta’ala. Tiap-tiap persamaan ini akan dikategorikan
kepada salah satu dari tiga relasi, yakni relasi ekuivalen, relasi umum-khusus mutlak,
dan relasi umum-khusus satu sisi.
6. Univokasi dan Kemendasaran Wujûd
Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ memiliki kesamaan dalam salah satu aspek
paling sakral dalam metafisika pemikiran Islam, yakni pemahaman tentang wujûd
sebagai dasar realitas. Kedekatan itu paling terlihat adalah keidentikan pandangan
kemendasaran wujûd sebagai suatu sistem ontologi dan kesamaan acuan makna
wujûd sebagai suatu konsep univokal. Wujudiah Hamzah Fansûrî dan filsafat Mullâ
Sadrâ sama-sama menerima wujûd sebagai univokal, yakni jenis kata (penanda) yang
hanya memiliki satu acuan (petanda) pada realitias. Kesamaan inilah yang membuat
ajaran keduanya berkonsekuensi pada kesamaan ajaran yang meyakini wujûd itu
adalah tunggal. Wujûd yang tunggal itu adalah Wujud Mutlak, yakni Haqq Ta’alâ.
Haqq Ta’alâ adalah wujûd yang mutlak bersifat Tunggal. Selain-Nya adalah
manifestasi dari Wujûd-Nya.
Segala manifestasi itu oleh sistem Wujudiah dianalogikan sebagai bayangan
bagi wujûd yang nyata. Segala realitas alam adalah seperti bayangan dan cermin
adalah diri manusia. Diri manusia yang paling sempurna merefleksikan bayangan
adalah al-insân al-kâmîl. Hal ini dapat terjadi karena al-insân al-kâmîl adalah wujûd
yang paling bersih sehingga dapat menghasilkan pantulan paling sempurna dari
Wujûd Ilahi. Dalam hal ini, imajinasi manusia sempurna adalah sangat utama karena
dapat menangkap suatu gambaran paling sempurna dari Hakikat Ilahi. Realitas yang
menjelma di alam materi adalah pengungkapan diri Haqq Ta’alâ yang merupakan
satu-satunya Hakikat Realitas696. Pengungkapan Diri Ilahi ini paling terang dapat
dilihat adalah oleh manusia sempurna yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad697.
Dalam sistem Hamzah Fansûrî, alam semesta memiliki wujûd. Akan tetapi,
wujûd yang dimiliki bukan wujûd hakiki, melainkan hanya sebagai wujûd wahmî.
Yang disebut dengan alam semesta adalah batu, kursi, kertas, dan sebagainya. Itu
semua memiliki wujûd sehingga dapat menjelma, tetapi mereka hanyalah bayangan
wujûd698. Alam semesta dapat terpancar karena adanya cermin, yakni diri manusia
sempurna. Pancaran tersebut menghasilkan bayangan Haqq Ta’alâ. Alam semesta
695 Meskipun penggunaan istilah antara dua pemikir ini berbeda dalam pengakuan
masing-masing atas eksistensi alam potensial, namun terkadang mereka menggunakan istilah-
istilah yang bersinggungan. Misalnya, Mullâ Sadrâ juga menggunakan istilah ‘ayan tsabitah
dan Hamzah Fansûrî menggunakan istilah mumkin al-wujûd. 696 Chittick, The Self-Disclosure of God: Principles of Ibn Al-’Arabi’s Cosmology…,
15. 697 Chittick, The Self-Disclosure of God: Principles of Ibn Al-’Arabi’s Cosmology…,
403. 698 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 282.
176
sebagai bayangan Haqq Ta’alâ tidak dapat dipahami, kecuali oleh orang-orang yang
menempuh penyucian diri. Mereka yang melakukan penyucian diri seperti berusaha
membersihkan permukaan cermin. Makin bersih cermin maka akan menjadi sarana
yang baik untuk memantulkan bayangan Ilahi699.
Dalam skema Mullâ Sadrâ, realitas alam semesta yang majemuk adalah
himpunan dari wujûd dan dan mâhiyâh. Apabila pengetahuan hanya terbatas pada
pengenalan mâhiyâh semata, sebenarnya itu adalah hijab untuk mengenal wujûd.
Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ mengetahui dan menyadari wujûd melalui
pengalaman langsung (hudhûrî) adalah mereka yang telah membersihkan diri dari
kecenderungan duniawi yang menjadi hijab bagi pengenalan wujûd. Jauh sebelum
para filosof eksistensialis di Barat memperkenalkan konsep kesadaran diri, Hamzah
Fansûrî dan filsafat Mullâ Sadrâ telah memperkenalkan konsep kesadaran dan
pengenalan diri700. Pengenalan diri ini bertujuan bahwa segala sesuatu yang
disandang diri, termasuk pengetahuan-pengetahuan konseptual yang dimiliki adalah
bersifat wahmî.
“Barang siapa yang mengenal dirinya, maka telah mengenal Tuhannya.”701
Pengenalan ini bukanlah pengenalan atribut-atribut yang melekat pada diri. Atribut-
atribut itu, seperti nama yang diberikan orang tua, gelar yang diberikan masyarakat,
pangkat yang diberikan lembaga, dan sebagainya semuanya bersifat wahmî.
Sejadinya yang nyata adalah Diri. Diri yang dimaksud bukan pula organ tubuh, kulit,
dan tulang. Diri itu adalah kesadaran Haqq Ta’alâ. Hal ini tidak sama dengan objek
yang disadari702.
Dalam sistem Mullâ Sadrâ, segala entitas dan realitas alam semesta menjadi
majemuk adalah karena proyeksi mental. Inteleksi menciptakan batas-batas bagi
wujûd dan membentuk aksiden-aksiden padanya, lalu diberikan nama. Sejatinya,
realitas eksternal hanyalah satu dan mendasar, yakni wujûd703. Proyeksi mental itulah
yang disebut bayang-bayang oleh Hamzah Fansûrî. “Sungguhpun pada zahirnya ada
ia berwujûd, tetapi wahmî juga, bukan wujûd haqiqi; seperti bayang-bayang dalam
chermin, rupanya ada hakikatnya tiada.”704 Apabila masih menerima kemajemukan
alam semesta sebagai eksistensi yang hakiki, itu berarti belum dapat mengenal
hakikat. Bahkan, apabila masih mengakui bahwa kedirian sebagai eksistensi yang
hakiki, juga belum dapat mengenal hakikat. Karena pada hakikatnya, wujûd yang
hakiki hanya dinisbahkan pada Haqq Ta’alâ. Sementara selainnya adalah wujûd
wahmî.
Fenomena-fenomena alam semesta tentunya adalah hasil konstruksi pikiran
manusia yang melahirkan suatu justifikasi705. Demikian juga dengan kekhasan setiap
entitas yang menjadi dasar pembangunan definisi, pada satu sisi dianggap sebagai
proyeksi mental. Misalnya, aktivitas meringkik pada kuda dan aktivitas
699 Hakiki, “Insan Kamil Dalam Perspektif Syaikh Abd Al-Karim Al-Jili.”…, 175-186. 700 Açıkgenç, Being and Existence in Ṣadrā and Heidegger…, 87. 701 Açıkgenç, Being and Existence in Ṣadrā and Heidegger…,, 107. 702 Açıkgenç, Being and Existence in Ṣadrā and Heidegger…, 198. 703 Sadrâ, Mullâ, Al-Masya’ir…, 3. 704 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 282. 705 Nasution, Filsafat Ilmu Pengetahuan…, 21–22.
177
menggonggong pada anjing, adalah aktivitas yang muncul pada level aksiden. Karena
itu, kekhasan itu menjadi wilayah tinjauan ilmu hushûlî sehingga segala
kemajemukan alam adalah bentukan persepsi pikiran dari aktivitas inteleksi.
Dalam analogi Hamzah Fansûrî, menjadi raja, menjadi menteri, menjadi gajah,
menjadi kuda, menjadi benteng, dan menjadi bidak sejatinya “… asalnya kayu
sepuhun jua. Maka dilarik berbaga-bagai; dinamainya raja, dan menteri, dan gajah,
dan kuda, dan tir dan baidaq. Asalnya kayu sekerat juga dijadikan banyak.”706 Yang
melarik itu adalah aktivitas inteleksi. Lalu, setelah inteleksi melariknya menjadi
berbagai-bagai, dinamailah kuda, batu, kursi, dan sebagainya makhluk-makhluk di
alam. Namun sejatinya, yang berbagai-bagai itu adalah wujûd yang dianalogikan
dengan kayu. Mullâ Sadrâ mengatakan bahwa aksiden itu adalah aktualitas substansi
maka dapatlah dipahami bahwa segalanya adalah dari substansi: akal, jiwa, materi
primer, bentuk, dan jasad. Kelima komponen substansi itu adalah berada dalam status
wujûd. Menjadi berbeda untuk setiap substansi entitas karena gradasi. Karena aksiden
adalah aktualitas substansi yang berada dalam wujûd, tentunya aksiden merupakan
bagian dari wujûd dari sisi eksistensinya, bukan gejala-gejala aksiden yang dipersepsi
indra707.
Bila konsep hakikat sederhana dikaitkan dengan gradasi wujûd, dapat dibuat
skema gradasi dalam konsep hakikat sederhana. Makin jauh segala sesuatu dengan
hakikat sederhana maka segala sesuatu menjadi makin majemuk. Sebaliknya, makin
dekat segala sesuatu dengan basit al-haqîqah maka makin sedikit keberagaman dan
menjadi makin sederhana708. Pola yang mirip dengan skema emanasi ini mungkin
dapat dicari kemiripannya dalam analogi dalam Wujudiah Hamzah Fansûrî tentang
buah catur, makin rendah tingkatan biji catur, makin banyak jumlahnya. Misalnya,
raja dan ratu yang tinggi tingkatannya hanya berjumlah satu, selanjutnya yang lebih
rendah, yakni gajah, benteng, dan kuda berjumlah dua. Sementara bidak yang paling
rendah jumlahnya paling banyak, yaitu delapan709.
Sebab itulah, pada sisi analisis intelektual, gejala-gejala aksiden dari realitas
makhluk-makhluk di alam semesta, seperti “kualitas”, yakni jawaban terhadap
pertanyaan “bagaimana?” terhadap sesuatu, seperti baunya, suhunya, dan wataknya;
“kuantitas”, yakni ukuran atau volume; “relasi”, yaitu keberhubungan sesuatu dengan
sesuatu yang lain; “tempat”, seperti pulpen di atas meja; “waktu”, seperti pada pukul
20.00; “posisi”, seperti tegak atau miring atau duduk atau berdiri; “kepemilikan” atau
“posesi”, seperti pulpen milik Ahmad; “aktif”, seperti api menghanguskan; dan
“pasif”, seperti api dipadamkan. Semua aksiden itulah yang membentuk nama-nama,
seperti “raja”, “menteri”, “gajah”, “kuda”, “benteng”, dan “bidak”. Sejatinya, semua
itu hanya nama-nama karena pada hakikatnya semua itu adalah kayu. Demikian juga
706 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 294. 707 Nasution, Filsafat Ilmu Pengetahuan…, 14. 708 Jabir, Wahdah Al-Wujûd Ibn ‘Arabî Dan Filsafat Wujûd Mulla Sadrâ…, 79–80. 709 Pierre Dangauthier et al., “TrueSkill through Time: Revisiting the History of
Chess,” in Advances in Neural Information Processing Systems 20 - Proceedings of the 2007
Conference (NIPS Proceedings, 2009), 1–8.
178
alam menjadi beragam karena inteleksi, lalu diberi nama-nama yang berbagai-bagai,
namun hakikat semuanya adalah wujûd yang tunggal710.
Dalam filsafat Mullâ Sadrâ, pengetahuan didefinisikan sebagai hadirnya
subjek kepada objek. Maka dari itu, meniscayakan status persoalan ini berada dalam
ranah ontologi. Dalam hal ini, tentunya realitas wujûd, baik dalam kesatuannya
maupun dalam gradasinya berada dalam status eksistensi. Karena itu, alam semesta
juga dianggap sebagai keberadaan, bukan ketiadaan ataupun objek yang diragukan.
Sama seperti Wujudiah Hamzah Fansûrî, epistemologi filsafat Mullâ Sadrâ menolak
sikap sofis yang mengakui realitas hanya proyeksi mental. Kedua ajaran tersebut juga
menolak sikap skeptis yang meragukan eksistensi realitas711.
Kemajemukan alam semesta yang dianalogikan dengan tumbuhan,
digambarkan Hamzah Fansûrî muncul dari ‘Ilmû Bâsîth yang dianalogikan dengan
tanah, dan Wujûd Bâsîth dianalogikan dengan air. Dalam pertemuan wujûd dan ilmu,
menjelmalah alam semesta. Sama halnya seperti dalam pertemuan air dan tanah terbit
tumbuh-tumbuhan. Aneka macam tumbuhan, aneka warna, dan beragam rasa
buahnya menjelma sebagai keberagaman dari air.
Hamzah Fansûrî mengatakan bahwa ajarannya itu berbeda dengan ajaran ilmu
kâlâm yang membedakan wujûd Tuhan dengan wujûd makhluk. Karena bila
membedakan wujûd Tuhan dengan wujûd makhluk, akal manusia akan memberikan
kesan bahwa wujûd Tuhan itu terbatas, yaitu batasannya adalah wujûd makhluk.
Dengan mengatakan, “Tanah itulah asal wujûd sekalian bejana itu”, Hamzah Fansûrî
ingin memberikan jalan keluar untuk mengatasi kebingungan tersebut bahwa wujûd
Tuhan itu sama dengan wujûd makhluk. Akan tetapi, wujûd yang dimaksud bukanlah
hal-hal yang ditangkap pancaindra. Karena hal-hal yang ditangkap pancaindra itu
bukan wujûd, melainkan aksiden-aksiden wujûd yang menjadi berbagai bentuk yang
majemuk sebagaimana kendi, buyung, periuk, tempat, dan bejana yang menjadi
beragam nama karena bentuk-bentuknya saja.
Ajaran Mullâ Sadrâ dalam mempertegas bahwa yang mendasari realitas adalah
wujûd, memberikan argumen, di antaranya adalah karena pada realitas eksternal yang
memberikan efek adalah wujûd, bukan mâhiyâh712. Sementara Hamzah Fansûrî tidak
membuktikan secara burhanî dalam makna sistem Arstotelian bahwa yang mendasari
realitas adalah wujûd sehingga tidak perlu menyampaikan argumentasi-argumentasi
yang sesuai dengan kaidah filsafat Peripatetik. Hamzah Fansûrî menegaskan bahwa
wujûd itu hanya satu, sementara penampakan-penampakan realitas yang mejemuk
adalah bayangan atau tajallî wujûd yang satu itu713. Bagi Hamzah Fansûrî,
kemajemukan pada alam hanyalah penamaan-penamaan. Penamaan-penamaan ini
sebenarnya adalah kesadaran bahwa kemajemukan itu hanyalah proyeksi mental dari
wujûd yang satu. Segala perabotan, seperti kendi, buyung, periuk, tempat, dan bejana
sebenarnya hanya nama-sama. Hakikatnya adalah tanah714. Demikian juga buah
710 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 294. 711 Gharawiyan, Pengantar Memahami Buku Daras Filsafat Islam…, 57. 712 Thabâthabâ’î, Bidâyah Al-Ḥikmah…, 19. 713 Herawati, “Concerning Ibn ’Arabi’s Account of Knowlegde of God (Ma’rifa) Al
Haqq.”…, 219. 714 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 268.
179
catur, seperti raja, menteri, gajah, kuda, benteng, dan bidak hanya penamaan karena
hakikatnya adalah kayu715. Dalam hal ini, Mullâ Sadrâ dan Hamzah Fansûrî sepakat
bahwa realitas eksternal diisi oleh satu wujûd, sementara kemajemukan itu adalah
proyeksi mental meskipun menghasilkan kesimpulan Mullâ Sadrâ menerima
kesatuan dan gradasi wujûd, sementara Wujudiah Hamzah Fansûrî menerima
Kesatuan Wujûd yang manifestasinya terjadi dalam bentuk ta’ayyûn.
Wujûd kharijî dalam istilah Mullâ Sadrâ, yakni alam semesta yang disebut
athar oleh Hamzah Fansûrî, menjadi beraneka ragam sebagai pancaran cahaya Ilahi,
menjadi siang dan malam, maksudnya adalah alam semesta menjadi berbagai-bagai
jenis, ada yang disebut baik, ada yang disebut buruk, semuanya berada dalam Sifat-
Sifat Jamâl dan Jalâl yang muncul dari Rahman dan Rahim. Himpunan dua sifat itu
dianalogikan, seperti himpunan air dan tanah yang menumbuhkan berbagai jenis
kayu-kayuan. Meskipun sebagiannya manis, sebagiannya pahit, asalnya tetap
(isti’dad) dari air dan tanah716.
Kemajemukan alam dari kemajemukan Nama-nama dan Sifat-sifat.
Kemajemukan ini digambarkan sebagai kemajemukan dalam ketunggalan wujûd
dalam skema Mullâ Sadrâ717. Meskipun majemuk, semua kemajemukan itu mengalir
di dalam ketunggalan. “Adapun Dhat Allah Amat suchi,” kata Hamzah Fansûrî718.
Analoginya seperti bahr al-‘amiq, yakni laut yang dalam. Dzat Haqq Ta’alâ tidak
terjangkau. Dia tiada terhingga dan tiada berkesudahan.
Mullâ Sadrâ dengan mudah dapat menjelaskan bagaimana kemajemukan itu
muncul karena dia berpandangan bahwa objek pengetahuan sebenarnya adalah
berada dalam diri subjek719. Kemajemukan itu dibentuk oleh fakultas jiwa dalam
ranah inteleksi. Pembentukan ini terjadi karena pada realitas eksternal yang nyata
adalah satu wujûd yang bergradasi. Gradasi ini terjadi karena perbedaan
kecenderungan dari sifat-sifat Ilahi.
Bahkan, penjelasan-penjelasan Mullâ Sadrâ tentang munculnya kemajemukan
dari ketunggalan mirip dengan pandangan Wujudiah720. Keberadaan kemajemukan
objek dalam diri subjek itu tentunya diinspirasi oleh sistem Wujudiah yang telah
digambarkan oleh Ibn ‘Arabî. Di antara analogi yang digunakan Ibn ‘Arabî untuk
menggambarkan kejadian kemajemukan dari ketunggalan adalah angka. Yang
merupakan realitas hakiki adalah satu. Satu hadir pada setiap angka lainnya. Setiap
angka lainnya bertopang pada satu. Semua angka kembali kepada angka satu.
Gambaran inilah yang dapat diduga sepertinya menginspirasi Mullâ Sadrâ
715 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 294. 716 Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri…, 151. 717 Rahman, The Philosophy of Mullâ Sadrâ (Sadr Al-Din Al-Shirazi)…, 141–142. 718 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 269. 719 Mullâ Sadrâ, Al-Hikmah Muta’aliyyah Fî Al-Asfâr Al-’Aqliyyah Al-Arba’ah Vol.
3…, 249. 720 Pandangan ini dikemukakan oleh Muhammad Nur Jabir. Dia mengatakan bahwa
kemajemukan hadir dari ketunggalan, oleh Mullâ Sadrâ berasal dari Nafs al-Rahman. Konsep
Nafs Al-Rahman sebenarnya adalah konsep dalam ’irfân. Jabir, Wahdah Al-Wujûd Ibn ‘Arabî
Dan Filsafat Wujûd Mulla Sadrâ.., 28.
180
menggambarkan gradasi wujûd karena skema analogi kesatuan dan kemajemukan
angka identik dengan skema gradasi wujûd721.
Realitas kemajemukan adalah pada kecenderungan Sifat-sifat dan Nama-nama.
Hamzah Fansûrî mengatakan, hal-hal yang dalam sensasi manusia dianggap baik
adalah karena kecenderungan Jamâl. Hal-hal yang dalam sensasi manusia dipandang
sebagai yang kurang baik, seperti cobaan dan teguran adalah karena kecenderungan
Jalâl. Namun demikian, semuanya muncul dari Rahman dan Rahîm melalui napas
Mahakasih. Adapun Rahman adalah segala himpunan Jalâl dan Rahim adalah segala
himpunan Jamâl722.
Dalam Wujudiah, alam semesta memiliki wujûd karena pemberian Haqq
Ta’alâ. Prosesnya adalah melalui tajallî Haqq Ta’alâ melalui Ilmu-Nya. Objek
pengetahuan-Nya adalah ‘ayân al-tsabîtah yang merupakan sumber segala modalitas
realitas eksternal yang majemuk. Sebagai objek pengetahuan Tuhan, tentunya
semuanya berada dalam Wujûd-Nya723. Hal ini sesuai dengan gambaran Mullâ Sadrâ
bahwa objek pengetahuan itu berada dalam diri subjek724. Sebagaimana suatu
mâhiyâh yang muncul dari persepsi sehingga memunculkan pengetahuan, demikian
juga alam semesta sebagai wujûd berada dalam wujûd Haqq Ta’alâ. Tidak terpisah,
dan bahkan “dalam” Diri-Nya725. Perbedaannya adalah, pengetahuan manusia adalah
pada menangkap aksiden dari wujûd. Sementara pengetahuan Tuhan yang menjadi
alam adalah pada hakikatnya, yakni pada Wujûd-Nya. Namun demikian, mâhiyâh
yang menjadi modus pengetahuan yang berada dalam diri manusia, juga tidak dapat
disebut ketiadaan karena mâhiyâh itu adalah cara intelek menangkap wujûd, yakni
dengan melimitasinya sedemikian rupa726. Dalam hal ini, limitasi bukan hanya
kecenderungan kreativitas inteleksi, melainkan karena gradasi dalam wujûd menurut
skema Mullâ Sadrâ727 atau kecenderungan Sifat-sifat dan Nama-nama dalam skema
Hamzah Fansûrî728.
Kemajemukan yang hadir dari kecenderungan-kecenderungan Nama-nama
dan Sifat-sifat dianalogikan Hamzah Fansûrî, “Seperti seorang Muhammad
namanya; jika ia ber’ilmû, ‘alîm namanya; jika ia pandai, utus namanya; jika ia tahu
menyurat, katib namanya; jika ia berniaga; saudagar namanya.”729 Persis seperti
satu orang yang sebutannya berbagai-bagai, tergantung pada hal-hal yang dapat
721 Kesatauan mengalir pada kemajemukan dan kemajemukan kembali kepada
kesatuan dalam gambaran taskîk al-wujûd Mullâ Sadrâ mirip dengan skema analogi angka
satu mengalir dalam angka-angka lainnya, dan semua angka kembali kepada angka satu dalam
gambaran Ibn ’Arabi. Lihat, Jabir, Wahdah Al-Wujûd Ibn ‘Arabî Dan Filsafat Wujûd Mulla
Sadrâ, 27; Miswari, “Filosofi Komunikasi Spiritualitas: Huruf Sebagai Simbol Ontologi
Dalam Mistisme Ibn ’Arabî,” Al-Hikmah 9, no. 14 (2017): 12–30. 722 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 262–264. 723 Ansori, M. Afif, Tasawuf Falsafi Syaikh Hamzah Fansûrî…, 122. 724 Sadra, Al-Hikmah Al-Muta’âliyah Fî Al-Asfâr Al-‘Aqliyyah Al-Arba’Ah Vol. III…,
313. 725 Rahman, Filsafat Sadra…, 111. 726 Nasr, Islamic Philosophy From Its Origin to the Presen…t, 68–69. 727 Rahman, The Philosophy of Mullâ Sadrâ (Sadr Al-Din Al-Shirazi)…, 35–36. 728 M. Afif Ansori, Tasawuf Falsafi Syaikh Hamzah Fansûrî…, 87. 729 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 240.
181
diidentifikasi darinya. Ketika berilmu, disebut ‘alîm’, ketika memiliki keahlian
tertentu disebut utus, ketika suka menulis disebut katîb, ketika berdagang disebut
saudagar. Demikian juga nama-nama Allah karena menjadikan makhluk disebut
Khâliq. Demikian juga wujûd yang satu, ketika wujûd dapat dianalisis menjadi
berbagai perspektif, dari satu wujûd memunculkan keberagaman730.
Terkait dengan hubungan ketunggalan dan kemajemukan, konsep cahaya
dalam pandangan Abû Hamid al-Ghazalî menyatakan bahwa cahaya adalah sesuatu
yang melaluinya menjelma sesuatu. Secara metaforis, dalam skema cahaya terdapat
pemberi dan penerima cahaya. Namun secara riil, yang terjadi adalah pemberian
cahaya sehingga dalam gambaran Abû Hamid al-Ghazalî, cahaya hanya menjadikan
sesuatu menjadi tampak731. Sementara menurut Mullâ Sadrâ, cahaya adalah wujûd
dengannya segala sesuatu menjelma732. Pandangan Mullâ Sadrâ733 tentang cahaya
mirip dengan pandangan Hamzah Fansûrî. Ketika menggambarkan alam semesta
sebagai athar cahaya wujûd, Hamzah Fansûrî hendak mengatakan bahwa alam
semesta adalah suatu eksistensi yang mengada dan dengannya alam semesta terjadi.
Tidak ada sensasi pemberi dan penerima dalam gambaran Hamzah Fansûrî. Hal ini
karena, “Memberikan wujûd pada sekalian ‘alam,” yang dimaksudkan Hamzah
Fansûrî adalah suatu athâr, yakni sebagai konsekuensi wujûd yang terjadi dalam
Asma’, Af’al, Sifat734.
Perbedaan pandangan antara Hamzah Fansûrî dan mutakâllimîn dalam
mengorientasikan terminologi cahaya adalah bahwa Hamzah Fansûrî menggunakan
cahaya sebagai analogi wujûd Haqq Ta’alâ yang digambarkan dengan matahari dan
cahayanya. Meskipun inteleksi memisahkan matahari dan cahayanya, hakikatnya
adalah satu735. Demikian pula pandangan Hamzah Fansûrî dalam menggambarkan
wujûd Haqq Ta’alâ dan wujûd makhlûqat. Sementara dalam pandangan
mutakallimîn, matahari berbeda dengan cahayanya sehingga wujûd Tuhan dibedakan
dengan wujûd makhluk736. Konsekuensi dari pandangan mutakâllimîn tersebut
adalah meniscayakan keterbatasan bagi wujûd Tuhan. Batas wujûd Tuhan adalah
wujûd makhluk. Padahal, Wujûd Tuhan meliputi segala sesuatu. Hal itulah yang
membuat pandangan wujûd sebagai ekuivokal bermasalah.
Mullâ Sadrâ melihat bahwa wujûd yang tunggal pada realitas itu bergradasi
sesuai dengan perbedaan antar mâhiyâh. Bila merujuk kembali pada status gradasi
dalam Mullâ Sadrâ, dalam penafsiran tertentu maka mâhiyâh adalah produksi mental
semata yang sifatnya identik dengan status bayangan di dalam cermin dalam
pandangan Wujudiah Hamzah Fansûrî. Sebab itulah, beberapa pengkaji Mullâ Sadrâ
berkesimpulan bahwa filsafat Mullâ Sadrâ adalah pandangan yang menerima
730 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 240. 731 Abû Hamid al-Ghazalî, Misykât al-Anwâr fî Tawhîd al-Jabbâr, (Lebanon: Dâr al-
Fikr, 1994), 76-77. 732 Al-Mandary, Menuju Kesempurnaan: Pengantar Pemikiran Mullâ Sadrâ…, 140. 733 Seyyed Hossein Nasr, Al-Hikmah Al-Muta’aliyah Mullâ Sadrâ : Sebuah Terobosan
Dalam Filsafat Islam (Jakarta: Sadra Press, 2017), 130. 734 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 268. 735 Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri…, 128. 736 Al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansûrî…, 242.
182
kesatuan wujûd atau disebut dengan Wujudiah737. Namun, sebagian filosof Neo-
Sadrian sepakat bahwa filsafat Mullâ Sadrâ adalah menerima wahdah (kesatuan)
sekaligus taskîk (gradasi) wujûd738. Dalam sistem tasykîk, prinsipnya adalah
perbedaan adalah persamaan itu sendiri. Keragaman adalah ketunggalan itu sendiri.
Perbedaannya adalah pada sisi intensitas, prioritas, dan kesempurnaan. Dalam hal ini,
mengesankan bahwa keberagaman itu diterima Mullâ Sadrâ menunjukkan bahwa
ajarannya adalah tidak bisa dilepaskan dari varian filsafat karena sekaligus Mullâ
Sadrâ menerima kesatuan wujûd maka pada sisi ini Wujudiah Hamzah Fansûrî dan
filsafat Mullâ Sadrâ dapat ditemukan kesamaannya. Namun, kesamaan identik antara
keduanya adalah mereka sama-sama menerima wujûd sebagai univokal dan menjadi
dasar realitas.
Peneliti Mullâ Sadrâ, Cipta Bakti Gama mengatakan bahwa aksiomatik konsep
wujûd yang juga berstatus sebagai univokal tentunya meniscayakan ketunggalan
realitas wujûd sebagai acuan konsepnya739. Sehingga dalam hal ini, realitas wujûd
dalam filsafat Mullâ Sadrâ adalah tunggal740. Dengan demikian, pandangan ini mirip
dengan pandangan Hamzah Fansûrî yang menyatakan bahwa wujûd itu tunggal.
Sebagaimana raja, menteri, gajah, kuda, benteng, dan bidak adalah berasal dari kayu.
Demikian juga kendi, buyung, periuk, tempat, dan bejana adalah dari tanah741. Tâskîk
dalam wujûd dianggap maknanya tetap merupakan satu wujûd karena gradasi terjadi
pada tingkat intensitas, prioritas, potensialitas-aktualitas, dan sebagainya, yang mana
semua itu terjadi dalam wujûd. Sementara wujûd itu tunggal sehingga tâskîk juga
merupakan kesatuan wujûd. Bahkan, peneliti Mullâ Sadrâ lainnya, Muhammad Nur
Jabir mengatakan bahwa tasykîk al-wujûd adalah tahapan yang dilakukan Mullâ
Sadrâ untuk menjustifikasi Wahdah al-Wujûd yang merupakan esensi filsafat Mullâ
Sadrâ742.
Sesuai dengan aksiomatik pengetahuan tentang wujûd dalam epistemologi
Mullâ Sadrâ, tasykîk itu sendiri bersifat aksiomatik. Cipta Bakti Gama menjustifikasi
pandangan bahwa tasykîk itu bersifat aksiomatik dengan menunjukkan bahwa
sejatinya pengetahuan adalah tentang wujûd, bukan kategori-kategorinya karena
kategori itu hanyalah hasil proyeksi mental. Sementara itu, kategori adalah alasan
munculnya tasykîk743. Sebenarnya, filosof yang menerima kesatuan wujûd tidak
hanya Mullâ Sadrâ. Ibn Sînâ sendiri, bahkan Syihab al-Dîn al-Suhrawardî juga
menerima kesatuan wujûd. Sebagaimana dikemukakan Fazlur Rahman, Ibn Sînâ
mengatakan bahwa sesungguhnya wujûd adalah satu-satunya hakikat realitas yang
737 Diskursus hubungan Wahah al-Wujûd dan filsafat wujûd Mullâ Sadrâ , lihat, Labib,
Pemikiran Filsafat Ayatullah M.T. Misbah Yadzi…, 203–205; Jabir, Wahdah Al-Wujûd Ibn
‘Arabî Dan Filsafat Wujûd Mulla Sadrâ…, 113–114. 738 Konsep ini disebut Fazlur Rahman sebagai ambiguitas sistem tasykîk. Rahman, The
Philosophy of Mullâ Sadrâ (Sadr Al-Din Al-Shirazi), 34. 739 Gama, Filsafat Jiwa: Dialektika Filsafat Islam, Dan Filsafat Barat Kontemporer…,
115. 740 Sadra, Al-Masya’ir…, 3. 741 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 268. 742 Jabir, Wahdah Al-Wujûd Ibn ‘Arabî Dan Filsafat Wujûd Mulla Sadrâ…, 86–87. 743 Gama, Filsafat Jiwa: Dialektika Filsafat Islam, Dan Filsafat Barat Kontemporer…,
116–117.
183
dimiliki Tuhan. Sementara wujûd lainnya, sebagai mumkîn al-wujûd, wujûd mereka
diberikan oleh Tuhan744. Demikian juga Syihab al-Dîn al-Suhrawardî yang
menyatakan bahwa Tuhan adalah wujûd Murni. Bahkan, Syihab al-Dîn al-Suhrawardî
sempat mengatakan bahwa diri manusia juga merupakan wujûd murni dalam
intensitas yang berbeda745. Gagasan Syihab al-Dîn al-Suhrawardî tersebut sebenarnya
ikut menginspirasi Mullâ Sadrâ merumuskan konsep kemendasaran dan kesatuan
wujûd yang bergradasi. Namun sayangnya, Syihab al-Dîn al-Suhrawardî mengingkari
pandangannya sendiri itu ketika mengulas persoalan epistemologis dengan
mengatakan bahwa wujûd dalam ranah mental hanyalah gagasan umum yang tidak
memiliki acuan pada realitas eksternal746. Namun demikian, pemikir yang secara
konsisten mengakui kemendasaran wujûd adalah Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ.
Dalam hal pengakuan kemendasaran wujûd, persamaan keduanya dapat dikatakan
ekuivalen (identik).
Meskipun mengenai mengenai kesatuan wujûd, antara Hamzah Fansûrî dan
Mullâ Sadrâ tidak dapat dikatakan identik karena penerimaan Mullâ Sadrâ atas
kemajemukan (taskîk). Namun, apabila hanya pada status univokasi konsep wujûd
dan kemendasaran status wujûd pada realitas eksternal, relasi antara gagasan wujûd
Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ adalah relasi keidentikan (ekuivalen) karena secara
tegas keduanya meyakini bahwa konsep wujûd itu univokal. Sementara pada realitas
eksternal, keduanya juga berpandangan bahwa wujûd adalah dasar bagi realitas.
7. Pengenalan Diri sebagai Langkah Menuju Pengetahuan Sejati
Kesamaan lainnya antara ajaran Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ adalah
pentingnya pengenalan diri sebagai langkah awal memperoleh pengetahuan sejati.
Keberhasilan tahap pengenalan diri adalah sucinya jiwa dari berbagai kecenderungan
yang sejatinya tidak bermanfaat. Dalam gambaran Hamzah Fansûrî, manusia adalah
umpama perahu yang harus mempersiapkan bekal. Sementara Mullâ Sadrâ
menegaskan bahwa daya jiwa manusia memiliki potensi besar untuk menghasilkan
pengetahuan sejati.
Jiwa butuh terjadinya kesempurnaan jasad untuk mengaktual. Namun
selanjutnya, jiwa tidak membutuhkan jasad karena setiap materi adalah aksiden asing
maka itu mustahil bagi jiwa yang bersifat nonmateri. Kebutuhan jiwa pada materi
hanya pada awal aktualitasnya747. Bila terjadi kerusakan pada raga, tidak berpengaruh
pada jiwa yang telah aktual748. Sebab itulah, Hamzah Fansûrî menganjurkan untuk
mempersiapkan bekal pada diri manusia yang dianalogikan dengan perahu selama di
dunia yang dapat dianalogikan dengan daratan. Karena setelah kematian nanti atau
selama di lautan, bekal yang dimaksud, yakni amalan menjadi andalan selama
pelayaran di lautan, yakni ketika terjadinya kesempurnaan aktualitas jiwa.
744 Rahman, The Philosophy of Mullâ Sadrâ (Sadr Al-Din Al-Shirazi)…, 28–29. 745 Syihab al-Dîn al-Suhrawardî, “Hikmah Al-Isyrâq,…” 22. 746 Izutsu,Toshihiko, The Concept and Reality of Existence (Islamic Book Trus: Kuala
Lumpu, 2007), 175–176. 747 Sadra, Al-Syawâhid Al-Rubûbiyyah Fî Al-Manâhij Al-Sulûkiyyah…, 318. 748 Sadra, Al-Hikmah Muta’aliyyah Fî Al-Asfâr Al-’Aqliyyah Al-Arba’ah Vol. 8…,
225-226.
184
Hai muda arif budiman
Hasilkan kemudi dengan pedoman
Alat perahumu juga kerjakan
Di sanalah jalan membetuli insan
Perteguh juga alat perahumu
Hasilkan bekal air dan kayu
Dayung pengayuh taruh di situ
Supaya laju perahumu itu749
Filsafat Mullâ Sadrâ menerima fakultas jiwa sebagaimana digambarkan oleh
al-Hikmah al-Masya'iyyah, dan mengatakan bahwa bahwa persepsi adalah daya jiwa.
Kegiatan ini berada pada beberapa fakultas jiwa, yakni persepsi, imajinasi, estimasi,
dan inteleksi. Persepsi indrawi bersifat individual dengan gabungan materi dan
bentuk. Persepsi imajinasi bersifat fantasi individual, dengan telah melepaskan aspek
materi dan hanya menyimpan formanya750. Karya-karya Wujudiah Hamzah Fansûrî
yang merupakan sebuah informasi atas pengalaman hudhûrî tentunya disampaikan
melalui ilmu hushûlî. Dengan analogi-analogi yang disampaikan, Hamzah Fansûrî
ingin mengajak para pembacanya untuk memahami ajarannya751. Proses pemahaman
atas ajaran-ajaran tersebut melibatkan berbagai tingkatan daya jiwa. Pesan-pesan itu
ingin mengajak untuk menyadari bahwa berbagai analogi itu sebagai cara untuk
memudahkan pengetahuan atas hakikat ajaran yang dimaksud. Karena untuk
mencapai hakikat makna, adalah dengan melalui ilmu hudhûrî, bukan ilmu hushûlî.
Demikian juga Mullâ Sadrâ menggunakan pendekatan filsafat tujuannya juga untuk
menyampaikan pengalaman hudhûrî melalui ilmu hushûlî752.
Munculnya buih hanya sejenak saja, lalu kembali menjadi air. Sebenarnya,
demikianlah kehidupan di dunia dan segala aktualitas alam materi hanya bersifat
sementara. Mullâ Sadrâ mengatakan bahwa alam jasad hanya bersifat sementara.
Demikian juga Hamzah Fansûrî berpandangan bahwa makhluk secara zahir hanya
bersifat sementara dan akan kembali kepada batinnya. Zahirnya alam yang
dianalogikan dengan buih juga dianalogikan dengan pesuluk yang harus kembali
749 Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri…, 16. 750 Persepsi estimasi bersifat individual dengan melepaskan materi dan bentuk.
Persepsi inteksi adalah bersifat universal. Ketika dahaga, itu nama disebut estimasi. Ketika
membayangkan air, itu sedang berimajinasi. Ketika melihat air, itu namanya persepsi indrawi.
Ketika menalar bahwa air itu menghilangkan dahaga, itu namanya inteleksi. Kemajemukan
daya jiwa tidak menunjukkan keberagaman jiwa. Semua tingkatan pengetahuan adalah
kehadiran jiwa pada tingkatan yang berbeda. Miswari, Filsafat Terakhir…, 148. 751 Hamzah Fansûrî mengatakan bahwa analogi-analogi yang dibuat itu maksudnya
agar ajaran Wujudiah yang diajarkan dapat dipahami. Dalam hal ini, antara lain dia
mengibaratkan laut dan ombak sebagai kiasan bagaimana sebenarnya yang dituntut dari
pengetahuan atas ombak sebagai pengetahuan representasi adalah untuk memahami laut
sebagai kiasan dari hakikat dibalik objek representasi (ombak). 752 Al-Mandary, Menuju Kesempurnaan: Pengantar Pemikiran Mullâ Sadrâ …, 204.
185
(wasil) kepada air yang dianalogikan dengan Haqq Ta’alâ753. Maksudnya adalah,
seorang pesuluk harus benar-benar melenyapkan dirinya hingga tidak lagi
menemukan dualitas antara dirinya dan Haqq Ta’alâ. Bila masih menemukan
dualitas, itu artinya belum sempurna perjalanan spiritualnya754. Namun untuk
menghindari salah paham terhadap pemikirannya, Hamzah Fansûrî mempertegas
bahwa makna wasil juga hanya sebagai kiasan untuk menggambarkan bahwa seorang
sufi harus benar-benar mampu melenyapkan identitas-identitas kediriannya hingga
menyadari bahwa hanya Haqq Ta’alâ saja wujûd yang tunggal. Itulah yang dimaksud
dengan tauhid sejati. Untuk itu, syariat tetap harus dijaga dengan teguh755.
Namun demikian, Hamzah Fansûrî tetap menegaskan pentingnya syariat
karena syariat adalah jalan yang objektif untuk memadu manusia menuju makrifat.
Syariat juga merupakan standar berkehidupan karena sufi yang benar adalah dia yang
tetap melakukan kerja-kerja kemanusiaan756. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat
adalah jalan yang harus ditempuh untuk memperoleh pengetahuan sejati. Sementara
Mullâ Sadrâ mengatakan bahwa bahwa sufi muta’allih adalah dia yang melakukan
empat perjalanan, yaitu al-safâr min al-Khalq ilâ al-Haqq, yakni perjalanan dari
makhluk menuju al-Haqq; al-safar bi al-Haqq fî al-Haqq, yakni perjalanan dengan
al-Haqq dalam al-Haqq; al-safâr min al-Haqq ilâ al-Khalq bî al-Haqq, yakni
perjalanan dari al-Haqq menuju makhluk bersama al-Haqq; dan al-safâr bi al-Haqq
fî al-khalq, yakni perjalanan dalam makhluk bersama al-Haqq. Perjalanan terakhir ini
menunjukkan bahwa tingkat tertinggi perjalanan spiritual adalah dalam aktivitas
kemanusiaan guna transendensi umat manusia757.
Dalam hal ini, Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ menekankan pentingnya
pengenalan diri atau perjalanan ke dalam diri untuk meraih pengetahuan sejati.
Perbedaannya hanya konsep yang digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah
tersebut. Hamzah Fansûrî menegaskan pentingnya syariat, tarekat, hakikat, dan
makrifat. Penjelasan makna dari empat perjalanan itu dijelaskan secara detail dalam
karyanya, Syarâb. Sementara Mullâ Sadrâ menjelaskan empat perjalanan spiritual
yang disebut asfar arba’ah secara detail dalam karyanya, Asfar758. Tujuan perjalanan
spiritual dan pengenalan diri yang disepakati Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ
dengan bahasa teknis masing-masing yang berbeda itu supaya manusia memperoleh
pengetahuan sejati yang disebut dengan ilmu presentasi (hudhûrî).
Mullâ Sadrâ dan Hamzah Fansûrî Fansûrî sama-sama berpandangan bahwa
pengenalan diri sebagai langkah awal menuju pencapaian pengetahuan sejati
(hudhûrî). Kemudian, keduanya juga sepakat siapa yang telah mencapai pengetahuan
sejati itu, untuk terjun ke tengah masyarakat agar masyarakat juga dapat memperoleh
pengetahuan tersebut.
753 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 294–295. 754 Schimmel, “Mystical Dimensions of Islam,”…, 448–450. 755 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 296. 756 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 296. 757 Dahlan Lama Bawa, “Pemikiran Pendidikan Mulla Shadra,” TARBAWI : Jurnal
Pendidikan Agama Islam 1, no. 2 (January 22, 2017): 123–128,
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/365. 758 ahlan Lama Bawa, “Pemikiran Pendidikan Mulla Shadra,”…, 39–41.
186
Namun, terdapat sedikit perbedaan antara keduanya dalam konteks ini.
Menurut tinjauan atas karya-karya mereka masing-masing, Hamzah Fansûrî lebih
menekankan untuk berproses melalui syariat dan tarekat. Sementara Mullâ Sadrâ
lebih menekankan untuk berproses melalui kesadaran rasional dalam sistem filsafat.
Dalam hal ini, relasi keduanya adalah relasi umum-khusus satu sisi. Sisi
perbedaannya adalah Hamzah Fansûrî mengajak melalui syariat dan tarekat karena
untuk mencapai makrifat prosesnya adalah melalui syariat dan tarekat. Sementara
Mullâ Sadrâ mengajak melalui pemahaman rasional-filosofis (filsafat) karena
orientasi pengenalan diri dalam sistem filsafat Mullâ Sadrâ adalah sebagai prasyarat
memperoleh pengetahuan sejati (hudhûrî). Sementara ilmu hudhûrî baginya
merupakan sebuah persiapan menemukan aksioma bagi penalaran filsafat.
8. Ilmu Hudhûrî sebagai Pengetahuan Sejati
Persamaan lainnya antara ajaran Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ adalah
pengakuan dan penerimaan bahwa pengetahuan sejati hanya bisa didapatkan melalui
ilmu presentasi (hudhûrî). Keduanya juga sepakat bahwa perjalanan menyucikan diri
sebagai langkah meraih pengetahuan tersebut. Pengetahuan hudhûrî inilah yang
menghantarkan pengetahuan pada hakikat realitas, yakni wujûd. Dalam ajaran Mullâ
Sadrâ, pengetahuan tentang wujûd adalah pengetahuan tentang hakikat realitas, yakni
eksistensi realitas. Sementara pengetahuan tentang mâhiyâh adalah limitasi mental
atas realitas yang membentuk identitas mental sehingga membedakannya dengan
mâhiyâh atau ke-sesuatu-an lainnya759. Demikian juga dalam analogi Hamzah
Fansûrî, secara hakikat seharusnya yang lebih dahulu diketahui adalah tanah yang
dianalogikan dengan wujûd, bukan kendi, buyung, periuk, tempat, dan bejana.
Namun, yang dialami adalah kendi, buyung, periuk, tempat, dan bejana lebih
terdahulu dikenal karena pengetahuan yang digunakan adalah pengetahuan
representasi (hushûlî) karena untuk mengetahui hakikat haruslah menggunakan ilmu
presentasi sehingga wujûd bisa dikenali. Pada hakikatnya, kendi, buyung, periuk,
tempat, dan bejana adalah tanah. Demikian juga secara hakikat, raja, menteri, gajah,
kuda, benteng, dan bidak adalah kayu. Namun untuk mengenal kayu, perlu dengan
ilmu presentasi (hudhûrî )760.
Pengetahuan representasi (hushûlî) sebagai suatu sistem epistemologi yang
dipisahkan dengan ontologi harus diterima sebagai transformasi konseptual761.
Karena itu, awal pengetahuan tentunya adalah mengetahui partikularitas (tajribî),
seperti mengetahui kendi, buyung, periuk, tempat, dan bejana atau mengetahui raja,
menteri, gajah, kuda, benteng, dan bidak. Selanjutnya, partikularitas-partikularitas
persepsi indrawi masuk ranah mental untuk dianalisis (burhanî) sehingga
menghasilkan konsep abstrak dari berbagai partikularitas. Misalnya, dalam
partikularitas raja, menteri, gajah, kuda, benteng, dan bidak, dapat dihasilkan konsep
759 Thabâthabâ’î, Bidayah al-Ḥikmah…., 19. 760 Izutsu, Sufism and Taoism: A Comparative Study of Key Philosophical Concepts…,
160. 761 Labib, Pemikiran Filsafat Ayatullah M.T. Misbah Yadzi…, 146.
187
abstrak “buah catur” atau dalam partikularitas kendi, buyung, periuk, tempat, dan
bejana menghasilkan konsep universal “perabotan”762.
Sistem kemenyatuan subjek dan objek yang menjadikan filsafat Mullâ Sadrâ
memiliki persamaan dengan dengan tasawuf Hamzah Fansûrî. Tasawuf Hamzah
Fansûrî meyakini bahwa realitas adalah aktualitas dari Haqq Ta’alâ dan keseluruhan
realitas adalah kehadiran Haqq Ta’alâ. Maka dari itu, Mullâ Sadrâ dalam hal ini
bertemu dengan tasawuf Hamzah Fansûrî karena mengakui bahwa pengetahuan
representasional hanyalah membentuk batasan bagi realitas yang tunggal sehingga
terproyeksi menjadi majemuk yang mana dengan itu aksidentalitas suatu identitas
terbentuk yang menjadikannya kesesuatuan (mâhiyâh)763. Sebab itulah, tasawuf
Hamzah Fansûrî mengatakan bahwa munculnya beragam bentuk perabotan rumah
tangga, seperti kendi, buyung, periuk, tempat, dan bejana hanyalah penamaannya.
Penamaan itu muncul dari perbedaan kondisi dalam tinjauan representatif. Sementara
hakikatnya, atau yang mendasar padanya adalah tanah764.
Pengetahuan representasi (hushûlî) dengan beragam tingkatannya, seperti
indra, inteleksi765, imajinasi, dan estimasi, berhasil mengidentifikasi partikularitas,
seperti kendi, buyung, periuk, tempat, dan bejana berarti hanya berhasil mengetahui
ke-apa-an sesuatu. Mengetahui ke-apa-an berarti belum mengetahui hakikatnya
karena mengetahui ke-apa-an hanya mengetahui mâhiyâh. Sementara pengetahuan
tentang mâhiyâh itu bersifat sekunder, sedangkan pengetahuan akan hakikat sesuatu
adalah berhasil mengetahui ke-ada-an atau eksistensinya (wujûd). Maka bila belum
mengetahui wujûd-nya, belumlah pengetahuan itu sejati. Mullâ Sadrâ mengatakan,
apabila belum mengetahui secara hudhûrî, belum dianggap memiliki pengetahuan766.
Begitulah pentingnya pengetahuan presentasi (hudhûrî) menurut Mullâ Sadrâ.
Karena itu, hanya mengetahui kendi, buyung, periuk, tempat, dan bejana, namun
belum mengetahui tanah, berarti belumlah memiliki pengetahuan atau baru
mengetahui raja, menteri, gajah, kuda, benteng, dan bidak, namun belum mengetahui
kayu, belum dapat disebut memiliki pengetahuan. Hanya bila setelah mengetahui
tanah yang menjadi hakikat kendi, buyung, periuk, tempat, dan bejana atau telah
mengetahui kayu yang menjadi hakikat raja, menteri, gajah, kuda, benteng, dan bidak,
barulah dapat disebut memiliki pengetahuan. Begitulah pentingnya pengetahuan
hudhûrî bagi Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ767.
Dengan demikian, aspek persamaan Mullâ Sadrâ dan Hamzah Fansûrî telah
dapat diidentifikasi pada ranah epistemologis. Keduanya menerima pengetahuan
representasi (hushûlî) adalah pengetahuan presentasi768. Hamzah Fansûrî
762 Nasution, Filsafat Ilmu Pengetahuan…, 15. 763 Thabâthabâ’î, Bidayah Al-Ḥikmah…, 18. 764 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 268. 765 Beserta ma’qulat awwal dan ma’qulat tsanî dan klasifikasi-klasifikasinya menurut
sistem epistemologi pemikiran Mullâ Sadrâ: Miswari, Filsafat Terakhir…, 179–180. 766 Sadra, Al-Syawâhid al-Rubûbiyyah fî al-Manâhij al-Sulûkiyyah…, 141. 767 Lihat juga, Labib, Pemikiran Filsafat Ayatullah M.T. Misbah Yadzi…, 168.; Taqi
Miṣbâḥ Yazdî, Al-Manhaj al-Jadîd fî Ta’lîm al-Falsafah Vol. 1…, 176. 768 Meskipun menurut Muhsin Labib, Muhammad Taqî Misbah Yazdî tidak
sepenuhnya menerima pendapat ini, namun Muhammad Taqî Misbah Yazdî tetap
menganggap ilmu presentasi tetap lebih signifikan dibandingkan ilmu representasi. Lihat,
188
menggambarkan tahapan-tahapan pencapaian pengetahuan presentasi (hudhûrî)
melalui syariat, tarekat, dan makrifat. Mullâ Sadrâ memberikan penjelasan rasional
mengenai posibilitas pencapaian pengetahuan presentasi769. Dalam skema wujûd,
jiwa termasuk mumkîn al-wujûd yang hanya aktual karena sesuatu selain dirinya.
Aktualitas jiwa terjadi karena sebab sempurna. Sebab sempurna terdiri atas sebab
material, sebab formal, sebab efisien, dan sebab final. Sebab efisien selalu inheren
pada jiwa. Bahkan, Mullâ Sadrâ menyebutkan sebab efisien sebagai Akal aktif ('aql
fa'al). Demikian juga dalam Wujudiah Hamzah Fansûrî yang menegaskan bahwa
Haqq Ta’alâ adalah yang memberikan wujûd kepada sekalian alam. Dalam hal ini,
menyesuaikan dengan konteks kausalitas Mullâ Sadrâ, demarkasi wujûd dapat
diperbandingkan dalam skema wujûd hakiki dan wujûd wahmî yang dibuat Syed
Muhammad Naquib Al-Attas, bahwasanya alam semesta adalah athar atau efek dari
wujûd yang tunggal770.
Dalam ajaran Mullâ Sadrâ, pengetahuan adalah kehadiran kausa sempurna
sebagai aktualitas jiwa. Status kausa efisien, yakni Akal aktif sebagai aktualisasi jiwa
selalu eksis. Karena bersifat immaterial, maka independen dari kausa material pada
awal aktualitasnya. Sebagai suatu aktualitas, jiwa identik dengan kausa forma
sehingga tidak mungkin hilang. Jiwa aktual mustahil tidak eksis. Eksistensi jiwa
aktual meniscayakan keberadaan objek pengetahuan dalam jiwa atau dalam skema
Hamzah Fansûrî yang disebut dengan athar771. Dengan menyebutkan alam sebagai
athar maka makna segala makhlûqat yang dianalogikan dengan kendi, buyung,
periuk, tempat, dan bejana, meskipun rupa-nya wahmî, ia adalah wujûd. Maksudnya,
rupa-rupa, atau bentuk-bentuk, adalah proyeksi mental yang dalam skema filsafat
disebut mâhiyâh772, namun hakikatnya adalah wujûd karena merupakan athar-Nya773
dalam istilah Hamzah Fansûrî atau mazahir Ilahiyah dalam istilah filsafat Mullâ
Sadrâ.
Mengikuti definisi tentang jiwa, dan menerima sistem kausalitas maka dapat
dikatakan bahwa pengetahuan adalah kehadiran wujûd secara presentasi tanpa
komposisi, kecuali dalam tinjauan mental. Dalam tinjauan mental, berbagai bentuk,
seperti kendi, buyung, periuk, tempat, dan bejana muncul. Namun sebagai suatu objek
pengetahuan, perabotan-perabotan itu adalah athar yang wujûd karena telah diberikan
wujûd. Oleh karena itu, “akibat” dalam tinjauan representasional, realitas
pengetahuan, dan konsepsinya bersifat identik seperti keidentikan substansi dan
Labib, Pemikiran Filsafat Ayatullah M.T. Misbah Yadzi…, 167–168 Bandingkan, ; Taqi
Miṣbāḥ Yazdī, Al-Manhaj al-Jadîd fî Ta’lîm al-Falsafah Vol. 1…, 176–177. 769 Yazdi, The Principles of Epistemology in Islamic Phlosophy: Knowledge by
Presence…, 25. 770 Al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansûrî…, 156–158. 771 Penjelasan tentang makna “athar” dalam skema Hamzah Fansûrî, lihat, Al-Attas,
The Mysticism of Hamzah Fansûrî…, 158–159. 772 Nasr, Islamic Philosophy From Its Origin to the Present…, 63. 773 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 268.
189
aksiden atau seperti rangkaian gradasi wujûd. Hal ini karena “akibat” dalam skema
Mullâ Sadrâ 774 itu identik dengan athar’775 dalam Wujudiah Hamzah Fansûrî.
Pandangan tersebut sejalan dengan sistem ontologi Mullâ Sadrâ bahwa realitas
itu tunggal sekaligus bergradasi. Komposisi substansi dan aksiden hanya terjadi pada
ranah mental. Misalnya, tembok putih adalah satu kesesuatuan pada realitas, lalu
hanya menjadi terkomposisi di ranah mental sehingga ketunggalan jiwa dan
keberagaman persepsi adalah wujûd yang satu dan bergradasi776. Kualitas dan aksi
sendiri adalah aksiden. Persepsi adalah aksi, sementara objek pengetahuan adalah
kualitas dari jiwa sehingga pengetahuan adalah kesatuan substansi dan
aksidennya. Kausa efisien dari setiap objek persepsi sesuai dengan surah ilmiyyah
dalam skema Wujudiah Hamzah Fansûrî777 adalah sesuai dengan entitas immaterial
yang disebut intelek aktif (‘aql fa'al) dalam istilah Mullâ Sadrâ778.
Kausa efisien dan kausa final adalah kausa eksternal. Kausa material dan kausa
final adalah kausa internal. Kausa eksternal terbagi menjadi kausa dekat dan kausa
jauh. Kausa dekat adalah hubungan langsungnya dengan efek menjadi pengetahuan
presentasi. Sementara kausa jauh adalah hubungan dengan efek melalui perantara
konsep yang menjadi pengetahuan representasi779. Dalam hal ini, filsafat Mullâ Sadrâ
menunjukkan bahwa pengetahuan itu adalah kesatuan subjek dan objek. Sejatinya,
pengetahuan adalah presentasi. Menjadi representasi karena mental mencoba
memahami pengetahuan dalam bentuk konsep. Sebagaimana analogi Hamzah
Fansûrî, pada hakikatnya pengetahuan adalah tanah. Menjadi kendi, buyung, periuk,
tempat, dan bejana karena mental berusaha memahami objek pengetahuan dalam cara
parsial780.
Sebagaimana dipegang oleh Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ, pengetahuan
adalah bertemunya gagasan abstrak sebagaimana dalam sistem ta’ayyûn Hamzah
Fansûrî: Dia menyaksikan (syuhûd) dirinya dan Dia juga yang disaksikan oleh Diri-
Nya781; dan dalam sistem ittihad aqil wa ma’qûl Mullâ Sadrâ: subjek yang
mengetahui (‘aqil) objek yang diketahui (ma’qûl), dan pengetahuan (‘aql) sebagai
774 Ali Arshad Riahi, “A Study of the Effect of Human Soul on External Objects :
Between Copenhagen School And Mullâ Sadrâ ,” Kanz Philosophia : A Journal for Islamic
Philosophy and Mysticism (2015): 19. 775 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 268. 776 Susilo, “Teori Gradasi : Komparasi antara Ibn Sina, Syihab al-Dîn al-Suhrawardî
dan Mullâ Sadrâ .”…, 159. 777 Al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansûrî…, 316–317. 778 Rustom, Mohammed, “Knowledge in Later Islamic Philosophy: Mullā Ṣadrā on
Existence, Intellect, and Intuition,” Iranian Studies 45, no. 3 (May 2012): 457–461,
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00210862.2012.655066. 779 Pembahasan lengkap tentang jenis-jenis kausa: Miswari, Filsafat Terakhir, 184–
185 Bandingkan, ; Gharawiyan, Pengantar Memahami Buku Daras Filsafat Islam…, 152–
155. 780 Gama, Filsafat Jiwa: Dialektika Filsafat Islam, Dan Filsafat Barat Kontemporer,
124. 781 Sandigu, Wahdah al-Wujûd : Polemik Pemikiran Sufistik Antara Hamzah Fansûrî
Dan Syamsuddin Sumatrani Dan Nuruddin Al-Raniri…, 63.
190
proses pengetahuan782. Baik dalam skema ta’ayyûn Hamzah Fansûrî maupun dalam
skema taskîk al-wujûd Mullâ Sadrâ, pengetahuan terjadi dalam wujûd. Namun, hal
itu merupakan pengetahuan yang subjek dan objeknya berada dalam status ontologis.
Dalam skema Hamzah Fansûrî adalah pengetahuan tentang tanah dan kayu783, atau
dalam skema Mullâ Sadrâ disebut sebagai wujûd784.
Di samping menjadikan pengetahuan hudhûrî sebagai sistem pengetahuan
hakiki, Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ juga menerima pengetahuan
representasional (hushûlî). Pengetahuan yang dapat diperoleh melalui
representasional (hushûlî) adalah pengetahuan mengenai realitas materi yang
diperoleh melalui indra, inteleksi, dan imajinasi785. Dalam sistem hushûlî,
pengetahuan tentang kendi, buyung, periuk, tempat, dan bejana, sebagai bentuk-
bentuk pengetahuan partikular (juz’i). Pengetahuan indrawi yang memersepsikan
partikularitas disebut sebagai ilmu tajribî. Ranah ini disebut juga dengan observasi.
Sains mengutamanakan pendekatan ini786. Selanjutnya, dalam analisis inteleksi dari
partikularitas itu menjadi pengetahuan pengetahuan umum atau abstrak (kullî)
“berbagai-bagai” dapat disebut sebagai konsep “perabotan”. Konsep “perabotan”
sebagai konsep abstrak merupakan kesempurnaan partikularitas. Ranah ini disebut
dengan burhanî. Filsafat dan matematika berada dalam ranah ini.
Objek yang dipersepsikan dengan indra, inteleksi, dan imajinasi, adalah
pengetahuan dalam pembahasan pengetahuan representasi787. Dalam sistem
representasi, indra, inteleksi, dan imajinasi menjadi pendekatannya. Dalam skema
Mullâ Sadrâ, objek pengetahuannya disebut dhihnî karena merupakan proyeksi indra
dan akal. Objek-objek pengetahuan itu meskipun disebut dhihnî, ia bukan merupakan
ketiadaan mutlak788. Sejalan dengan Hamzah Fansûrî, meskipun menyebutkan objek-
objek partikular itu (kendi, buyung, periuk, tempat, dan bejana) sebagai disebut
dengan “nama” dan “rupa” yang sifatnya wahmî, tidak dapat dikatakan ‘adam atau
ketiadaan mutlak. Hal ini karena sebagai aktualitas pengetahuan, seperti kendi,
buyung, periuk, tempat, dan bejana yang menjadi analogi alam semesta, berada dalam
level martabat dalam skema ta’ayyûn789.
Dengan menegaskan bahwa alam semesta adalah wujûd yang meskipun
bentuk-bentuknya beraneka ragam itu adalah proyeksi mental maka ketika
782 Al-Walid, Tasawuf Mulla Shadra: Konsep Ittihad Al-’Aqil wa Al-Ma’qul dalam
Epistemologi Filsafat dan Makrifat Ilahiyyah, 114. 783 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 268. 784 Sadrâ, Mullâ, Al-Masya’ir (Teheran: Amir Kabir, t.t.), 2–3. 785 Labib, Pemikiran Filsafat Ayatullah M.T. Misbah Yazdi…, 144–145. 786 Brambor, Thomas, William Roberts Clark, dan Matt Golder, “Understanding
Interaction Models: Improving Empirical Analyses,” Political Analysis 14, no. 1 (January 4,
2006): 63–82,
https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S1047198700001297/type/journal_articl
e. 787 Pembahasan relasi dan demarkasi ranah ontologi dan ranah epistemologi. Lihat,
Labib, Pemikiran Filsafat Ayatullah M.T. Misbah Yadzi…, 144–147. 788 Jabir, Wahdah Al-Wujûd Ibn ‘Arabî Dan Filsafat Wujûd Mulla Sadrâ…, 26. 789 Sandigu, Wahdah al-Wujûd : Polemik Pemikiran Sufistik Antara Hamzah Fansûrî
Dan Syamsuddin Sumatrani Dan Nuruddin Al-Raniri…, 63.
191
mengatakan keberagaman itu sebagai bentuk, ia bersifat wahmî karena bentuk itu
muncul dari proyeksi mental. Namun, bila yang diacu adalah eksistensinya, ia ada
dan bahkan menjadi dasar realitas790. Bentuk-bentuk partikular itu muncul dari
analisis inteleksi yang merupakan hasil tinjauan aksidentalitas. Aksiden-aksiden itu
adalah buatan inteleksi sehingga disebut wahmî. Akan tetapi, substansinya adalah
wujûd sehingga alam semesta disebut ada dan nyata791.
Melalui pendekatan hushûlî, realitas alam semesta yang merupakan wujûd
dikenal melalui aksiden-aksidennya. Aksiden-aksiden itulah yang menjadi pembeda
antarentitas792. Dalam skema Mullâ Sadrâ, pembeda wujûd disebut mâhiyâh. Melalui
mâhiyâh setiap entitas-entitas dapat dikenali melalui ilmu representasi793. Melalui
ilmu representasi diketahuilah buah catur, seperti raja, menteri, gajah, kuda, benteng,
dan bidak794. Semua itu direpersepsi melalui fakultas jiwa terendah, yakni indra. Indra
dan inteleksi membedakan raja dengan menteri, membedakan gajah dengan kuda, dan
membedakan benteng dengan bidak. Perbedaan-perbedaan itu muncul dari perbedaan
aksiden-aksidenya sehingga membentuk mâhiyâh-nya masing-masing795.
Hasil analisis ilmu hushûlî yang menjelmakan berbagai mâhiyâh: raja, menteri,
gajah, kuda, benteng, dan bidak, ingin dikatakan Hamzah Fansûrî bahwa itu semua,
“Asalnya kayu sepuhun jua. Maka dilarik berbaga-bagai; dinamainya raja, dan
menteri, dan gajah, dan kuda, dan tir dan baidaq. Asalnya kayu sekerat juga
dijadikan banyak796”. Menjadi banyak karena inteleksi telah “melarik” wujûd yang
dianalogikan dengan kayu dalam inteleksi sehingga dalam konsep partikular menjadi
“raja”, “menteri”, “gajah”, “kuda”, “benteng”, dan “bidak” yang sebenarnya pada
realitas eksternal adalah entitas yang satu, yaitu kayu. Sementara dalam konsep
universal, raja, menteri, gajah, kuda, benteng, dan bidak diabstraksikan menjadi
konsep “buah catur”.
Sebenarnya, maksud Hamzah Fansûrî adalah ingin mengatakan bahwa dasar
realitas adalah satu, yakni wujûd yang dianalogikan dengan kayu797. Sementara
kemajemukan yang hadir dalam persepsi, sesuai dengan skema Mullâ Sadrâ798,
adalah berkat karakteristik inteleksi yang menghasilkan aksiden-aksiden untuk tiap-
tiap entitas sehingga menghasilkan kesan berbagai-bagai799. Berbagai perbedaan di
alam yang muncul dari entitas yang satu itu dinamai berbagai nama: batu, gunung,
meja, kursi, dan sebagainya. Disebut “raja”, disebut “menteri”, disebut “gajah”,
disebut “kuda”, disebut “benteng”, dan disebut “bidak”. Meskipun muncul berbagai
nama, hakikatnya itu adalah wujûd yang dari Haqq Ta’ala.
790 Sadrâ, Mullâ, al-Masya’ir…., 3. 791 Alam semesta atau makhluk-makhlum bukan ketiadaan ('adam) tetapinyata, karena
diberikan wujûd oleh Haqq Ta’âlâ. 792 Izutsu, Struktur Metafisika Sabzawari…, 16. 793 Nasr, Islamic Philosophy From Its Origin to the Present…, 63. 794 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 294. 795 Nasr, Seyyed Hossein “Existence (Wujūd) and Quiddity (Māhiyyah) in Islamic
Philosophy,” International Philosophical Quarterly (1989): 409. 796 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…., 294. 797 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…., 294. 798 Izutsu, Struktur Metafisika Sabzawari, 153. 799 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 294.
192
Hamzah Fansûrî telah menegaskan bahwa karyanya itu hanyalah sebuah
penjelasan konseptual tentang pengalaman hudhûrî. Sementara bila ingin
mengalaminya secara langsung, perlu dengan mencari guru yang benar dalam
suluk800. Syihab al-Dîn al-Suhrawardî sebelumnya telah menegaskan bahwa untuk
mencapai pengalaman tersebut, diperlukan pelatihan yang ketat801. Pentingnya
pengalaman tersebut, untuk dibedakan dengan segala penjelasan penjelasan
tentangnya adalah seperti tamsilan Jalal al-Dîn Rûmî antara mencium mawar dengan
mencium tulisan: m.a.w.a.r802.
Sementara itu, Hamzah Fansûrî dalam Asrâr telah memberikan sedikit
panduan menempuh jalan tersebut, selain dengan mencari guru yang tepat yang dapat
membimbing ke dalam suluk, yaitu dengan menjauhi kecenderungan dunia,
memperbanyak puasa, dan menerapkan kehidupan yang zuhud803. Karena hanya
dengan pengalaman itulah, Haqq Ta’alâ yang tiada awal, tiada akhir, tidak dekat,
tidak jauh, dan tidak di enam arah (sebagaimana analogi buah bundar) menjadi dapat
dikenal sejauh potensi yang dimiliki seorang insan804.
Dalam penerimaan atas perlunya ilmu hudhûrî sebagai sumber pengetahuan
sejati, Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ memiliki kesamaan. Namun, hubungan
kesamaan ini tidak benar-benar identik. Hal ini karena bagi Mullâ Sadrâ, ilmu
hudhûrî hanya menjadi landasan aksiomatis dalam filsafatnya sebagai alternatif bagi
kegagalan definisi dalam pembangunan filsafat. Sementara bagi Hamzah Fansûrî,
ilmu hudhûrî adalah tujuan akhir dari perolehan pengetahuan. Dengan demikian,
relasi dari kesamaan ini adalah relasi umum-khusus mutlak karena bagi Mullâ Sadrâ,
ilmu hudhûrî hanya hanya sebagai modal persiapan dalam berfilsafat. Sementara bagi
Hamzah Fansûrî, ilmu hudhûrî itu adalah fondasi pembangunan sekaligus merupakan
kesempurnaan dari pengetahuan. Sehingga dalam hal ini, ilmu hudhûrî bagi Mullâ
Sadrâ merupakan bagian dari pengetahuan karena dia juga mengembangkan
gagasannya melalui filsafat dalam pendekatan burhanî.
9. Eksistensi Alam Potensial
Wujudiah Hamzah Fansûrî dan filsafat Mullâ Sadrâ sama-sama menerima
eksistensi alam potensial yang menjadi sumber menjelmanya realitas alam semesta
yang majemuk. Keduanya memiliki istilah masing-masing dalam mengistilahkan
alam potensial itu. Mullâ Sadrâ sesuai dengan skema Wujudiah mengistilahkannya
dengan ‘ayan al-tsabitah. Sementara Mullâ Sadrâ yang menjelaskan ajarannya dalam
perspektif filsafat mengistilahkannya dengan materi primer (hayûlâ). Sistem ini telah
dibicarakan sejak filsafat Yunani. Dalam pemikiran Islam, sistem tersebut
diakomodir dengan baik dalam filsafat Islam. Dalam tasawufi filosofis, sistem
tersebut juga coba dikaitkan dengan dalil-dalil dalam agama, khususnya dari hadis
qudsi, seperti:
800 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 234. 801 Sholikhin, Muhammad, Menyatu Diri Dengan Ilahi (Yogyakarta: Narasi, 2010),
538. 802 Kartanegara, Mulyadhi, Menyelami Lubuk Tasawuf, (Jakarta: Erlangga, 2006), 123. 803 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 279. 804 Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri…, 126.
193
“Terdapat suatu ketika Tuhan itu Ada, sementara belum ada apapun bersama-
Nya. Sebenarnya kondisi demikian juga terjadi saat ini. Demikian juga nanti
dan kapan pun.805”
Allama Sir Muhammad Iqbal mengutip pernyataan Abû Yazid al-Bistamî
dengan maksud ingin mengatakan bahwa kemajemukan realitas alam dan bergulirnya
waktu dalam kehidupan manusia sama sekali tidak mengubah apa pun bagi kondisi
Tuhan806. Situasi ini persis seperti yang digambarkan Hamzah Fansûrî bahwa
sekalipun situasi air berubah menjadi uap, menjadi awan, menjadi hujan, menjadi
sungai, kembali lagi ke laut, sama sekali tidak mengubah kemurnian lautan807.
Penjelasan itu untuk menunjukkan bahwa perubahan dalam keberagaman tidak
mengganggu ketetapan Ilahi. Eksistensi alam potensial itu dijadikan bagian dari
argumentasinya. Sebagaimana menganalogikan laut sebagai Wajib al-Wujûd yang
tiada apa pun berubah darinya meskipun berbagai bentuk ombak808, demikian juga
analogi buah yang bundar juga digunakan untuk menyatakan maksud yang sama809.
Bahwa Haqq Ta’alâ dianalogikan dengan:
“… buah [yang] buntar; tiada berhujung dan tiada berpuhun, tiada permulaan
dan tiada berkesudahan, tiada di tengah dan tiada tepinya, dan tiada hadapan
dan tiada belakangnya, tiada kiri dan tiada kanan, tiada atas dan tiada
bawahnya.”810. Ketetapan dan ketidakberhinggaan Haqq Ta’alâ yakni Qadîm
tidak berlaku baginya perubahan dan keberhinggaan811.
Dalam pengalaman fânâ, pesuluk dan ‘urafa tidak lagi mengidentifikasi alam,
merujuk istilah Mullâ Sadrâ, fakultas indrawi, fakultas inteleksi, fakultas imajinasi,
dan fakultas inteleksi812. Semua fakultas itu merupakan fakultas jiwa yang memiliki
batasan. Semua fakultas itu ditempuh melalui ilmu hushûlî813. Karakteristiknya
adalah pembentukan entitas yang meniscayakan perbedaannya dengan entitas yang
lain (nonkontradiksi).
Hamzah Fansûrî menganalogikan kondisi tersembunyi seperti biji. Haqq
Ta’alâ sebagai Dzat yang tidak dapat dijangkau oleh siapa pun dianalogikan dengan
bahr al-amiq. Sebagai entitas yang sama sekali tidak dapat dijangkau, Hamzah
Fansûrî menyebut ranah itu sebagai lâ ta’ayyûn, yakni kunhî al-dhatî al-haqqî814.
Tidak ada yang dapat menjangkau. Sementara dalam filsafat, ranah tersebut sama
sekali tidak disentuh. Meskipun filsafat Mullâ Sadrâ menerima keniscayaan ilmu
805 Iqbal, Rekonstruksi Pemikiran Relegius dalam Islam…, 129. 806 Iqbal, Rekonstruksi Pemikiran Relegius dalam Islam…, 54. 807 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 274. 808 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 274. 809 Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri…, 126. 810 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 240. 811 Mufrodi, “Alam Semesta Dan Keabsolutan Tuhan.”…, 335. 812 Rahman, The Philosophy of Mullâ Sadrâ (Sadr Al-Din Al-Shirazi)…, 225. 813 Nasution, Filsafat Ilmu Pengetahuan…, 13. 814 Fansûrî, “Syarâb Al-Asyiqîn…, 315.
194
hudhûrî815, dikaitkan dengan pengalaman fânâ ‘urafâ maka ‘urafâ mengaku bahwa
wilayah yang dapat mereka jangkau dalam pengalaman itu hanyalah ‘ayân al-
tsabîtah. Mereka mengakui adanya maqâmât di atasnya, tetapi tidak dapat
menjangkaunya816.
Hal ini diperkuat dengan pernyataan Hamzah Fansûrî yang mengakui bahwa,
jangankan sufi, nabi, dan malaikat muqarrabîn sekalipun tidak dapat menjangkau
Dzat Haqq Ta’alâ. Hal ini didukung dengan hadis Nabi Muhammad yang
mengatakan, “Maha Suci Engkau, tiada kukenal Diri-Mu dengan sempurna
kenal”817. Situasi ini digambarkan Hamzah Fansûrî dalam ‘Syarâb al-Asyiqin’:
“Ketahui bahwa kuhi Dhat Haqq Subhanahu wa Ta’ala ini dinamai Ahlul
Suluk la ta’ayyûn. Maka dinamai la ta’ayyûn karena budi (burhanî), dan
bichara (bayanî), ‘ilmu (nazarî), dan ma’rifat (‘irfanî) kita tiada lulus
kepadanya. Jangankan ilmu dan ma’rifat kita, anbiya dan uwliya pun
hayran.”818
Maka dengan itu, adalah mustahil membahas tentang Dzat Haqq Ta’alâ
sebagaimana dianalogikan Hamzah Fansûrî dengan bahr al-amiq. Segenap potensi
yang dimiliki manusia tidak membuka peluang untuk itu. Ranah yang dapat dijangkau
adalah maqamat ta’ayyûn. Ranah ini dianalogikan dengan laut yang telah berelasi
dengan ombak.
Pada pembahasan ta’ayyûn yang telah menjadi manifestasi atau tajallî itulah
yang dapat menjadi pembahasan tasawuf, filsafat, dan logika. Pada ta’ayyûn pertama,
terdapat ‘Ilmû, Wujûd, Syuhûd, dan Nûr. Dalam status ini, dengan adanya ‘Ilmû maka
terdapat tiga entitas, yakni “yang mengetahui (alîm)”, “yang diketahui (ma’lûm)”,
dan hubungan keduanya disebut dengan “ilmû (pengetahuan)”. Skema ini sesuai
dengan konsep ittihâd aqîl wa ma’qûl dalam sistem filsafat Mullâ Sadrâ819.
Kesatuan yang mengetahui dan yang diketahui dianalogikan oleh Hamzah
Fansûrî dengan laut dan ombak. Laut dianalogikan dengan yang mengetahui dan
ombak dianalogikan dengan yang diketahui. Hubungan keduanya disebut dengan
pengetahuan820. Dengan demikian, ombak yang menjadi analogi pengetahuan dari
Haqq Ta’alâ, berada dalam manifestasi Haqq Ta’alâ sehingga dapat diketahui
manusia. Demikian pula dengan alam semesta dan segenap makhluk dapat dikenal
manusia karena telah menjelma. Persis seperti laut, yang dapat dilihat adalah ombak
pada permukaannya821.
Dalam Syarâb, objek pengetahuan Tuhan itu disebut dengan ‘ayân al-tsabîtah,
yaitu sumber tetap yang menjadi potensi segala sesuatu atau disebut suwar ilmiyah
815 Nasution, Filsafat Ilmu Pengetahuan…, 87. 816 Chittick, The Self-Disclosure of God: Principles of Ibn Al-’Arabi’s Cosmology…,
354. 817 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 271. 818 Fansûrî, “Syarâb Al-Asyiqîn"…, 315. 819 Muthahhari, Filsafat Hikmah: Pengantar Pemikiran Shadra…., 112. 820 Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri…, 154. 821 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 252.
195
yaitu gambaran ilmu Tuhan atau disebut haqîqat al-asyâ’, yaitu hakikat segala
sesuatu atau disebut rûh idhâfî, yaitu sumber segala jiwa822. Dalam skema Hamzah
Fansûrî, semua itu disebut ta’ayyûn awwal yang dianalogikan dengan laut. Ketika
laut timbul dinamakan ombak, yakni ketika Tuhan memandang Diri-Nya. Ketika
memancarkan Diri-Nya kepada ‘ayân al-tsabîtah disebut dengan rûh idhâfî, itu
dianalogikan dengan uap air laut823 dan berhimpun di udara disebut dengan ‘ayân al-
tsabîtah yang dianalogikan dengan awan karena padanya berhimpun segala ketetapan
yang hendak memancar ke alam. Ketika rûh idhâfî dengan ‘ayân al-tsabîtah keluar
dengan kûn, dianalogikan dengan air hujan. Ketika mengalir di bumi, yakni ‘ayan
tsabiytah, rûh idhafî, dan isti’dad aslî, dianalogikan dengan sungai. Semua itu
kembali ke laut yang tetap seperti pada pemberian Haqq Ta’alâ yang tidak sedikit
pun mengubah Diri-Nya824.
Gambaran kejadian semesta seperti analogi di atas hendak menunjukkan
bahwa wujûd alam semesta berasal dari Haqq Ta’alâ yang dianalogikan dengan laut
dan semuanya kembali kepada laut. Kejadian kemajemukan dalam kesatuan ini
sangat mudah ketika dipahami dalam sistem taskîk al-wujûd Mullâ Sadrâ, yang mana
segala kemajemukan berasal dari ketunggalan, ketunggalan mengalir di dalam
kemajemukan, dan kemajemukan kembali kepada ketunggalan825. Karena itu, segala
ta’ayyûn itu sejatinya berada dalam Haqq Ta’alâ. Tidak ada apa pun yang terpisah
dari-Nya. Dalam hal ini, Hamzah Fansûrî juga hendak menyanggah pandangan
teologis yang mengatakan makhluk-makhluk berasal dari ketiadaan, menjadi ada, lalu
kembali tiada826. Problem ini pernah menjadi perdebatan antara pemikiran Ibn Sînâ,
Abû Hamid al-Ghazalî, dan Ibn Rusyd827. Pandangan Hamzah Fansûrî dan penganut
tasawuf filosofis lainnya dalam hal ini sejalan dengan para filosof, termasuk Mullâ
Sadrâ828.
“Laut dan ombak keduanya rafîq829”, yakni dalam tinjauan epistemologis
ketika menggunakan bayanî dan burhanî, ombaklah yang terlihat dan terpahami.
Sementara ketika dalam ilmu hudhûrî, seperti yang dialami pesuluk dan para filosof
muta’allih, ombak menjadi tak terlihat, mereka tenggelam ke dalam lautan. Dalam
kondisi ini, kesadaran diri menjadi lenyap. Mereka dalam kondisi fânâ830.
Dalam kondisi ini, dapatlah dipandang hakikat wujûd, bukan wujûd wahmî.
Pada pengalaman itu, tidak ada limitasi dan persepsi serta inteleksi, imajinasi, dan
822 Darinyalah bermanifestasi menjadi sumber jasmani sekalian makhluk. Lihat,
Fansûrî, “Syarâb Al-Asyiqîn"…, 316. 823 Hamzah Fansûrî menyebutnya asap. Lihat, Fansûrî, “Syarâb Al-Asyiqîn"…, 316. 824 Fansûrî, “Syarâb Al-Asyiqîn…, 316–317. 825 Rahman, The Philosophy of Mullâ Sadrâ (Sadr Al-Din Al-Shirazi)…, 35–36. 826 Fansûrî, “Syarâb Al-Asyiqîn…, 317. 827 Syamsuddin Arif, “Filsafat Islam Antara Tradisi Dan Kontroversi,” TSAQAFAH 10,
no. 1 (May 31, 2014): 1,
http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/61. 828 Dalam hal ini, pemikiran Mullâ Sadrâ sependapat dengan para filosof lainnya yang
meyakini bahwa yang tidak memiliki mustahil dapat memberikan, sehingga dari ketiadaan
mustahil muncul keberadaan. Miswari, Filsafat Terakhir, 36. 829 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 274. 830 Chittick, The Sufi Doctrine of Rumi .., 71.
196
estimasi. Jalan untuk dapat menempuh pengetahuan itu adalah dengan menghindari
kecenderungan hati kepada kenikmatan materi, kenikmatan indrawi, kenikmatan
inteleksi, kenikmatan imajinasi, dan kenikmatan estimasi831. Syihab al-Dîn al-
Suhrawardî membuat aturan yang sangat ketat untuk dapat memperoleh pengetahuan
itu. Sementara Mullâ Sadrâ telah mengasingkan diri dari kesibukan duniawi untuk
memperoleh pengalaman hudhûrî. Oleh sebab itu, dia dapat membangun filsafat yang
menggantikan posisi definisi dengan hudhûrî sebagai elemen mendasar merumuskan
proposisi832.
Perdebatan tentang ‘ayân al-tsabîtah telah lama menjadi diskursus
intelektualisme Islam di Kepulauan Indonesia. Sejak Kesultanan Samudra Pasai,
persoalan itu sudah muncul dan melibatkan para cendekiawan Samudra Pasai, Negeri
Melayu, Jawa, dan dunia. Keterlibatan ulama Pasai tentang persoalan tersebut
menunjukkan pada masa itu, diskursus intelektual telah berada pada level tertinggi.
Tentunya hal ini tidak terjadi dengan seketika, tetapi telah mengalami proses yang
panjang dari penyelenggaraan pendidikan Islam tinggi hingga kondisi politik yang
kondusif833. Tentunya orang yang sedang kelaparan dan menderita krisis ekonomi
tidak punya waktu membicarakan persoalan metafisika tinggi, seperti ‘ayân al-
tsabîtah. Orang-orang dalam kondisi politik yang kacau juga tidak sempat
membahasnya. Maka dari itu, dapat menjadi bukti bahwa, sebelum ekspansi
Majapahit, Portugal, dan Aceh Darussalam, Samudra Pasai adalah sebuah kerajaan
yang memiliki kemakmuran yang baik834. Tentunya karena pada masa itu mereka
mendominasi pos pelayaran Jalur Sutra Selat Malaka. Kondisi politik juga menjadi
stabil (sebelum atau sesudah) konflik dengan Maharaja Bakoy dan Syaikh ‘Abd al-
Jalîl835. Samudra Pasai memiliki perguruan tinggi Islam yang menghasilkan ilmuwan
besar di Dayah Blang Pria sehingga pembahasan metafisika tinggi menjadi lumrah di
sana. Bahkan, pembahasan tersebut berdampak pada persoalan politik. Atau
sebaliknya, persoalan politik yang ikut menyeret diskursus keagamaan sehingga
memunculkan konflik dengan Maharaja Ahmad Bakoy dan Syaikh ‘Abd al-Jalîl 836.
Dalam dunia Islam dengan perspektif yang luas, perdebatan metafisika telah
berlangsung jauh sebelumnya hingga persinggungan filsuf, seperti Al-Kindî dan para
teolog, ahli fikih, dan ahli hadis837. Dominasi teologi yang bernuansa doktrin
diberikan alternatif dalam nuansa filosofis oleh Al-Fârâbî dan Ibn Sînâ. Nuansa
filosofis tentunya sangat dipengaruhi oleh warisan filsafat Yunani838. Sebenarnya,
mutakallimîn, ahli fikih, dan ahli hadis juga banyak mengambil manfaat dari filsafat
831 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 283–284. 832 Al-Mandary, Menuju Kesempurnaan: Pengantar Pemikiran Mullâ Sadrâ…, 205. 833 Ali Hasjmy mengatakan bahwa Dayah Blang Pria yang terletak di Geudong Pasai,
tidak jauh dari pusat kerajaan Kesultanan Samudra Pasai, adalah Perguruan Tinggi terbesar di
Asia Tenggara sekitar abad ke-13 dan abad ke-15, Hasjmy, Bunga Rampai Revolusi Dari
Tanah Aceh…, 57–59. 834 Kosmopolitanisme Kesultanan Samudra Pasai. Lihat, Said, Aceh Sepanjang Abad
Vol. I…, 70–73. 835 Hasjmy, Ruba’i Hamzah Fansûrî.., 1. 836 Hasjmy, Ruba’i Hamzah Fansûrî.., 1. 837 Jackson, What Is Islamic Philosophy?..., 33–34. 838 Kartanegara, Mengislamkan Nalar: Sebuah Respon Terhadap Modernitas…, 60.
197
Yunani. Akan tetapi, mereka tetap mengkritik filosof karena kesimpulan-kesimpulan
pemikiran mereka jauh berseberangan dengan paham mutakallimîn839.
Para filosof menyatakan bahwa alam telah sedia bersama Wajîb al-Wujûd.
Alam mustahil merupakan sesuatu yang baru karena bila demikian, meniscayakan
perubahan pada Wajîb al-Wujûd” yang mana itu mustahil sebagaimana pandangan
mutakallimîn, filosof, dan ‘urafâ. “Alam juga mustahil berasal dari ketiadaan karena
yang tidak memiliki mustahil dapat memberikan”. Proposisi ini juga diterima
mutakallimîn, filosof, dan sufi Wujudiah sehingga tidak ada alasan untuk menolak
pernyataan bahwa, “Alam telah mengada bersama Wajib al-Wujûd sejak asali.” Abû
Hamid al-Ghazalî membantah pandangan filosof yang menyatakan alam telah ada
sejak asali karena dalam Kehendak Allah yang tetap, alam itu niscaya belum ada
hingga menjadi ada.
Sebenarnya, para filosof hendak mengatakan bahwa Wajîb al-Wujûd sebagai
wujûd kekal dengan wujûd-nya senantiasa dalam kesibukan atau menjadikan alam
secara terus-menerus sehingga alam bukan terjadi dari ketiadaan, melainkan dari
sesuatu yang telah ada sebelumnya dan seterusnya840. Pandangan para filosof sesuai
dengan pengajar Wujudiah, termasuk Hamzah Fansûrî yang menyatakan bahwa
Haqq Ta’alâ selalu dalam kesibukan (shâ’n)841. Hamzah Fansûrî dan para penganut
Wujudiah lainnya berpandangan bahwa segala kebaruan kejadian alam semesta
adalah hal-hal yang tetap dalam ‘ayân al-tsabîtah. ‘Ayân al-tsabîtah adalah suatu
manifestasi Ilmu dari Haqq Ta’alâ. Ilmu, sebagaimana Sifat-sifat lainnya bersifat
tetap842. Karena bila sifat berubah, meniscayakan perubahan pada sifat. Posisi antara
sifat dan Zat, seperti gambaran Mullâ Sadrâ antara subjek dan predikat. Segala
predikat bergantung pada subjek. Misalnya seseorang bernama Ahmad, segala
predikasi yang diberikan kepadanya bergantung pada bagaimana kondisi Ahmad
diamati, lalu diberikan predikat kepadanya.
Mullâ Sadrâ dalam hal ini mengatakan bahwa kejadian alam semesta karena
Sifat-sifat dari Wajîb al-Wujûd, seperti Al-Murîd, Al-Karîm, dan Al-Muhsîn. Alam
semesta adalah aktualitas dari Nama-nama dan Sifat-sifat. Aktualitas alam berasal
dari alam immateri yang bersifat kekal bersama Nama dan Sifat. Sementara alam
materi itu baharu secara tempo karena waktu merupakan bagian dari aksiden.
Sementara itu aksiden adalah perangkat untuk alam materi843. Mullâ Sadrâ menerima
kekekalan eksistensi alam immateri sebagai konsekuensi dari kesatuan dan
kemajemukan wujûd dalam sistem gradasi (taskîk)844. Pandangan Mullâ Sadrâ yang
mengatakan alam jasmani itu baharu dan alam materi itu kekal sesuai dengan
pernyataan Hamzah Fansûrî bahwa secara lahiriah alam materi ini baharu, namun
839 Harahap, Islam Dan Modrrnitas: Dari Teori Modernisasi Hingga Penegakan
Kesalehan Modern…, 156. 840 Iqbal, Muhammad, Ibn Rusyd Dan Averroisme: Pemberontakan Terhadap Agama
(Medan: Cipustakan Media Perintis, 2011), 68–69. 841 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 276. 842 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 261–262. 843 Gama, Filsafat Jiwa: Dialektika Filsafat Islam, Dan Filsafat Barat Kontemporer…,
131. 844 Jabir, Wahdah Al-Wujûd Ibn ‘Arabî Dan Filsafat Wujûd Mulla Sadrâ…, 26–27.
198
secara batiniah ia kekal. “Adapun kata Ahlul Suluk, sungguhpun tiada ia mawjûd
pada zahirnya, tetapi pada batinnya ia mawjûd.”845 Dengan analogi pohon yang
akarnya, batangnya, cabangnya, dahannya, daunnya, rantingnya, dan buahnya sudah
terkandung dalam biji846. Hamzah Fansûrî menunjukkan ilmu Tuhan yang terbukti
melalui eksistensi alam semesta persis seperti seorang raja yang memiliki kekuasaan.
Apabila tidak memiliki kekuasaan, seseorang tidak dapat disebut sebagai raja.
Seseorang disebut sebagai raja karena memiliki kekuasaan. Hal ini dianalogikan
dengan bukti eksistensi ilmu Tuhan dengan eksistensi alam semesta847.
Aktualitas alam semesta sebagai aktualitas Ilmu Haqq Ta’alâ dianalogikan
oleh Hamzah Fansûrî dengan eksistensi sebuah bangunan dalam pikiran seorang utus.
Antara sang utus dan gambar bangunan itu adalah satu kesatuan mutlak. Gambar
bangunan itu adalah objek pengetahuan utus yang menyatu dengan sang subjek, yakni
utus. Ketika bangunan itu dibuat, itu merupakan aktualitas ilmu sang utus848.
Bagaimana Hamzah Fansûrî menganalogikan seorang utus dengan aktualitas suatu
bangunan, melalui skema kesatuan subjek dan objek dalam sistem Mullâ Sadrâ, dapat
menunjukkan orientasi analogi Hamzah Fansûrî tentang bagaimana alam semesta
mengaktual dengan ilmu dari Haqq Ta’alâ.
Dalam skema ittihâd aqîl wa ma’qul ditunjukkan Mullâ Sadrâ bahwa objek
pengetahuan berada dalam diri subjek849. Demikian juga dengan eksistensi alam
semesta berada dalam Ilmu Haqq Ta’alâ dalam bentuk ‘ayân al-tsabîtah. Dari ‘ayân
al-tsabîtah itu mengaktual menjadi realitas alam semesta850. Sebagai konsekuensi
dari kesatuan wujûd yang dipahami Mullâ Sadrâ bahwa wujûd manusia yang
merupakan kesatuan wujûd memiliki potensi perkembangan wujûd yang terus-
menerus dapat menjangkau alam yang dalam terminologi ‘irfân disebut ‘ayân al-
tsabîtah. Maka dari itu, dapat memiliki pengetahuan Ilahiah sesuai dengan
kemampuan aktualitas dirinya.
Kehidupan manusia di alam dunia dianalogikan Hamzah Fansûrî dengan
sebuah kapal yang sedang bersandar di dermaga. Bersandar hanya sementara karena
kapal harus menempuh lautan yang luas. Segala perbekalan harus dipersiapkan.
Demikian juga manusia harus mempersiapkan amal kebaikan sebagai bekal jiwa yang
menempuh tahap perjalanan selanjutnya bagi jiwa851. Mullâ Sadrâ dalam hal ini dapat
membantu menjelaskan secara rasional bagaimana jasad manusia di dunia ini bersifat
baharu sementara yang kekal adalah jiwanya. Hasan Zâdeh Amûlî852 menjelaskan
bahwa dalam pemikiran Mullâ Sadrâ, jasad hanya menjadi persiapan bagi jiwa dalam
845 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 247. 846 Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri…, 132. 847 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 253–254. 848 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 253–254. 849 Sadra, Al-Hikmah Al-Muta’âliyah Fî Al-Asfâr Al-‘Aqliyyah Al-Arba’Ah Vol. III…,
313. 850 Al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansûrî…, 263. 851 Abdul Hadi WM., Tasawuf yang Tertindas…, 168. 852 Hasan Zadeh Amuli, Sarh al-‘Uyûn fî Syarh Al-‘Uyûn (Qum: Markaz Intesyârât-e
Daftar-e Tablîghât-e Islâmî, 1421H), 273–275.
199
kariernya yang panjang. Jiwa memang membutuhkan jasad untuk awal aktualitasnya,
tetapi kontinuitas jiwa tidak bergantung pada jasad853.
Dalam filsafat Mullâ Sadrâ, jasad dipandang sebagai aktualitas jiwa. Tetapi
pada kelanjutan kariernya, jiwa tidak membutuhkan jasad. Buktinya adalah, ketika
terjadi masalah tertentu pada jasad, tidak berpengaruh pada kualitas jiwa. Misalnya,
ketika terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan amputasi pada bagian tertentu dari
jasad, pengetahuan tidak berkurang dengan kejadian itu854. Untuk itulah dapat
dipahami bagaimana kelanjutan karier jiwa terjadi terus-menerus setelah
meninggalkan jasad. Untuk itu, selama masih menyandang jasad yang dengannya
menunjukkan masih adanya potensialitas, segala amal kebaikan perlu dipersiapkan
persis seperti kapal yang masih sedang bersandar di dermaga. Bila nantinya kapal
telah berlabuh, tidak bisa lagi mempersiapkan perbekalan. Ketika jiwa sudah terpisah
dengan jasad, itu telah menjadi aktualitas murni. Ketika telah terpisah dengan jasad,
tidak bila lagi mempersiapkan perbekalan.
Dalam sistem kesatuan subjek dan objek, subjek yang mengetahui tentunya
adalah tunggal855. Sementara objek yang diketahui bisa beragam. Karena subjek dan
objek adalah tunggal, subjek dapat disebut yang dibagi sementara objeknya adalah
bagian. Dalam hal ini, subjek yang mengetahui yang dianalogikan dengan dapat
disebut sebagai sesuatu yang tersembunyi yang disebut sebagai kanzân makfî
(perbendaharaan tersembunyi). Sementara objek yang diketahui yang dianalogikan
dengan buih yang beragam corak, beragam warna, dan berbagai bentuk sejatinya
adalah aktualitas air. Demikian keberagaman alam semesta merupakan aktualitas dari
perbendaharaan tersembunyi.
Terkait bagian ini, jenis hubungan dalam kesamaan antara Hamzah Fansûrî dan
Mullâ Sadrâ adalah relasi ekuivalen. Meskipun masing-masing menggunakan bahasa
teknis dan pendekatan penjelasan yang berbeda, sama-sama memahami bahwa alam
potensial itu sudah eksis sejak sedia kala dan menjadi sumber bagi menjelmanya
realitas alam semesta.
10. Kefakiran Mutlak Makhluk kepada Khalik
Segala makhluk memperoleh wujûd dari Haqq Ta’alâ. Kebergantungan
makhluk kepada Khalik adalah kebergantungan eksistensial. Hamzah Fansûrî dan
Mullâ Sadrâ sama-sama menerima pandangan ini. Hamzah Fansûrî menganalogikan
kebergantungan makhluk seperti besi yang tunduk secara mutlak kepada tukang besi.
Mullâ Sadrâ menjelaskannya dalam konsep kefakiran akibat atas sebab. Dalam
pandangan Hamzah Fansûrî, segenap makhluk adalah seperti bayangan karena sama
sekali tidak memiliki kehendak atas dirinya. Segenap kejadian dan aktivitas makhluk
adalah benar-benar tunduk pada Haqq Ta’alâ. Makhluk yang sama-sekali tidak
memiliki daya dan kehendak oleh Hamzah Fansûrî dianalogikan dengan batu. Batu
benar-benar tunduk pada yang memegangnya.
Untuk memiliki kehendak harus memiliki ilmu, untuk memiliki ilmu harus
memiliki kehidupan, untuk memiliki kehidupan harus memiliki wujûd. Sementara
853 Mullâ Sadrâ, Al-Syawâhid Al-Rubûbiyyah fî Al-Manâhij Al-Sulûkiyyah, 310. 854 Amuli, Sarh Al-‘Uyûn fî Syarh Al-‘Uyûn…, 401. 855 Al-Walid, Tasawuf Mulla Shadra…,127.
200
semua makhluk tidak memiliki wujûd, kecuali Wujûd Haqq Ta’alâ.
Ketidakberdayaan makluk dalam gambaran Hamzah Fansûrî persis seperti posisi
kopula dalam sebuah kalimat dalam skema filsafat Mullâ Sadrâ. Kopula benar-benar
bergantung pada subjek meskipun dapat diberikan nama yang berbeda.
Kemajemukan nama predikat adalah hasil pengamatan dari gejala dan kondisi
subjek856. Ketidakberdayaan makhluk di hadapan Haqq Ta’alâ dalam skema Mullâ
Sadrâ juga dapat digambarkan seperti posisi akibat bagi sebab857. Sebab dapat
dinisbahkan kepada Haqq Ta’alâ. Sementara akibat dapat dinisbahkan kepada
makhluk-makhluk. Pada makhluk sejatinya adalah kehadiran Haqq Ta’alâ secara
menyeluruh sehingga jangankan memiliki kehendak, sang makhluk, bahkan tidak
memiliki wujûd858.
Seorang manusia sebagai makhluk dalam perjalanan spiritualnya harus
mendapatkan pengetahuan sejati, yakni kesadaran bahwa dirinya sama sekali tidak
memiliki daya, persis seperti suatu kopula yang benar-benar tunduk kepada subjek.
Karena memang sebagai makhluk, manusia persis seperti suatu akibat yang benar-
benar diisi oleh sebab sehingga sejatinya sang makhluk seperti akibat, benar-benar
bergantung pada sebab. Dalam ajaran Mullâ Sadrâ, sebab menjadi eksis karena fokus
peninjauan hanya pada sebab. Namun, bila ditinjau secara keseluruhan, yang tampak
hanyalah kehadiran sebab secara menyeluruh dan berlangsung secara terus-
menerus859.
Munculnya dua nama atau dua perspektif bukanlah hakikat yang nyata. Karena
pada hakikat yang nyata ada adalah Haqq Ta’alâ yang dianalogikan dengan emas.
Sementara eksistensi makhluk seperti batu. Apabila masih menemukan dualitas emas
dan batu, berarti dalam perjalanan spiritual, belum menemukan hakikat yang nyata860.
Apabila pesuluk telah mengalami fânâ, tidak ada apa pun yang dilihatnya, kecuali
emas. Tidak tampak lagi batu pada emas itu861. Dalam kondisi fânâ pesuluk insaf
bahwa dirinya dan segala makhluk benar-benar seperti batu: sama sekali tidak
memiliki kehendak, sama sekali tidak berdaya, dan tidak memiliki kekuatan, kecuali
pada Haqq Ta’alâ.
Kesamaan wujûd kopula dalam ajaran Mullâ Sadrâ dengan analogi buah catur
dan perabotan dalam Wujudiah Hamzah Fansûrî adalah keduanya merupakan
gambaran terhadap wujûd selain Tuhan. Semua makhluk dalam ajaran Mullâ Sadrâ
diibaratkan dengan kopula bagi subjek. Demikian juga Hamzah Fansûrî
menggambarkan buah catur dan perabotan seperti makhluk-makhluk. Mullâ Sadrâ
melihat dasar realitas adalah wujûd. Segala selain wujûd terjadi dalam wujûd862.
Demikian juga dalam Wujudiah Hamzah Fansûrî, segalanya adalah wujûd yang
856 Jabir, Wahdah Al-Wujûd Ibn ‘Arabî Dan Filsafat Wujûd Mulla Sadrâ…, 35. 857 Ibid., 74–76. 858 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”, 268. 859 Riahi, “A Study Of The Effect Of Human Soul On External Objects : Between
Copenhagen School And Mullâ Sadrâ ,”…, 19. 860 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 287–288. 861 Ibid., 288. 862 Sadra, Al-Masya’ir…, 10.
201
dianalogikan dengan kayu. Segala bentuk seperti raja, menteri, gajah, kuda, benteng,
dan bidak keseluruhannya adalah kayu. Semuanya terjadi dalam kayu863.
Dalam sistem kopula kausal Mullâ Sadrâ, sebab sebagai wujûd hakiki
memberikan wujûd kepada akibat sehingga kebergantungan akibat kepada sebab
adalah kebergantungan wujûd864. Demikian juga dengan kebergantungan buah catur
kepada kayu adalah kebergantungan wujûd. Yang memilliki wujûd dalam skema
analogi ini hanyalah kayu. Sementara raja, menteri, gajah, kuda, benteng, dan bidak
sama sekali tidak memiliki wujûd. Keseluruhan buah catur adalah kayu. Demikian
juga kebergantungan kendi, buyung, periuk, tempat, dan bejana pada tanah adalah
kebergantungan wujûd865. Kendi, buyung, periuk, tempat, dan bejana tidak memiliki
wujûd. Keseluruhan perabotan itu adalah tanah. Demikian juga setiap akibat adalah
kehadiran wujûd sebab866.
Gambaran ini juga mirip dengan sistem Wujudiah Hamzah Fansûrî dalam
analogi air. Pada hakikatnya, hanya ada satu wujûd yang dianalogikan dengan air.
Dalam analisis mental terdapat tiga entitas, yakni qasîm, maqsûm, dan syu'un.
Sebagai yang dibagi air disebut qasîm yang dianalogikan dengan laut. Sebagai
bagian, disebut dengan maqsûm yang dianalogikan dengan ombak. Aktivitas
pembagian disebut dengan syu'un yang dianalogikan dengan topan. Adapun air
tersebut adalah analogi untuk wujûd867. Karena itu, Mullâ Sadrâ dan Hamzah Fansûrî
menerima bahwa sejatinya sebagai hakikat realitas eksternal adalah wujûd yang
mendasar dan tunggal meskipun di dalamnya memunculkan banyak nama sebagai
aktivitas mental868.
Makhluk-makhluk menjadi wujûd karena diberikan wujûd oleh Haqq Ta’alâ.
Sesuai dengan skema ta’ayyûn rabi’ dan ta’ayyûn khamis869, pemberian wujûd ini
terjadi secara terus-menerus870. Begitu bergantungnya makhluk kepada Haqq Ta’alâ,
makhluk dapat disebut sebagai kefakiran mutlak. Kondisi ini oleh Hamzah Fansûrî
dianalogikan dengan kondisi buah catur. Buah catur sama sekali tidak memiliki daya
untuk mengendalikan dirinya. Buah catur benar-benar tunduk kepada pemain catur.
Buah catur sama sekali tidak dapat memiliki kehendak dan menggerakkan dirinya.
Semua kehendak dan geraknya mutlak bergantung pada kehendak dan digerakkan
oleh pemain catur. Sebagai akibat dari kayu, buah catur secara keseluruhan adalah
kehadiran kayu. Buah catur sendiri, raja, menteri, gajah, kuda, benteng, dan bidak,
sebagai akibat dari kayu secara mutlak bergantung pada kayu. Raja, menteri, gajah,
kuda, benteng, dan bidak, adalah kefakiran mutlak. Buah catur itu menjadi ada adalah
karena secara terus-menerus mendapatkan kayu. Persis seperti alam semesta yang
menjadi ada karena secara terus-menerus diberikan wujûd melalui Rahman dan
863 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”, 294. 864 Taqi Miṣbāḥ Yazdī, Al-Manhaj Al-Jadîd Fî Ta’lîm Al-Falsafah Vol. 1…, 70–74. 865 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 294. 866 Labib, Pemikiran Filsafat Ayatullah M.T. Misbah Yadzi…, 227–228. 867 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 275. 868 Sadra, Al-Masya’ir…, 3. 869 Sandigu, Wahdah al-Wujûd: Polemik Pemikiran Sufistik Antara Hamzah Fansûrî
dan Syamsuddin Sumatrani dan Nuruddin Al-Raniri…, 61–62. 870 Kejadian ini dianalogikan oleh Hamzah Fansûrî dengan aliran sungai yang mengalir
terus-menerus. Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…., 265.
202
Rahîm. Raja, menteri, gajah, kuda, benteng, dan bidak adalah akibat dari kayu. Kayu
sebagai sebab dapat disebut dengan wujûd mandiri (rabith). Raja, menteri, gajah,
kuda, benteng, dan bidak dapat disebut wujûd yang bergantung secara mutlak
(mustaqil). Dalam skema suatu proposisi, eksistensi raja, menteri, gajah, kuda,
benteng, dan bidak hanya sebagai kopula bagi subjek kayu871.
Meskipun menggunakan argumentasi melalui pendekatan yang berbeda,
Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ sama-sama beritikad bahwa makhluk itu benar-
benar fakir wujûd dan wujûd itu hanya dari Khalik. Karena itu, hubungan kesamaan
keduanya dalam konteks ini adalah relasi ekuivalen. Adapun Hamzah Fansûrî
menjelaskan kefakiran makhluk melalui pendekatan tasawuf Wujudiah. Sementara
Mullâ Sadrâ menjelaskannya melalui perspektif filsafat.
B. Perbedaan Wujudiah Hamzah Fansûrî dan Filsafat Mullâ Sadrâ
Sebenarnya, perbedaan antara Wujudiah Hamzah Fansûrî dan filsafat Mullâ
Sadrâ sangat banyak dan tidak dapat dihitung. Namun, perbedaan yang dianalisis
dalam penelitian ini adalah beberapa yang terkait dengan limitasi objek kajian.
Pertama adalah perbedaan konteks budaya. Perbedaan ini adalah niscaya dan dapat
dipahami secara umum karena konteks Melayu dan Persia sekitar abad ke-17
tentunya berbeda. Perbedaan ini tidak terlepas dari perbedaan dunia intelektual yang
memengaruhi keilmuan, pengajaran, dan karya-karya Hamzah Fansûrî dan Mullâ
Sadrâ. Kedua adalah perbedaan pemahaman atas status kemajemukan realitas
eksternal. Hamzah Fansûrî menegaskan realitas eksternal itu tidak nyata. Sementara
Mullâ Sadrâ ambigu dalam hal ini karena selain menerima ketunggalan, sekaligus dia
menerima kemajemukan realitas eksternal. Pada sisi penerimaan kemajemukan
realitas eksternal ini, pandangan Mullâ Sadrâ menjadi berbeda dengan Hamzah
Fansûrî yang dengan tegas menolak eksistensi kemajemukan. Ketiga adalah
perbedaan multiperspektif varian dan sasaran kritikan. Maksudnya adalah, setelah
melahirkan ajaran masing-masing, kondisi ajaran mereka berbeda. Meski sempat
ditolak sementara oleh sebagian kalangan, ajaran Mullâ Sadrâ selanjutnya diterima
dengan baik di negerinya. Ajaran tersebut hanya membuat para pengikutnya berbeda
pemahaman dalam memaknai ajaran Mullâ Sadrâ. Sebagian menganggapnya sebagai
ajaran tasawuf filosofis. Sebagian menganggapnya sebagai ajaran filsafat murni.
Sementara ajaran Hamzah Fansûrî yang sempat diapresiasi dengan baik, misalnya
oleh oleh Shams al-Dîn al-Sumatranî berubah menjadi ajaran yang dikritik secara
tajam oleh Nûr al-Dîn al-Ranîrî sehingga Wujudiah mengalami kemunduran, bahkan
masih dianggap sebagai ajaran yang tabu hingga hari ini. Semua perbedaan ini
digolongkan ke dalam relasi nonekuivalen karena tiap-tiap kondisinya berbeda.
1. Perbedaan Konteks Kebudayaan
Perbedaan utama yang secara umum tidak terbantahkan adalah konteks
penyebaran ajaran Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ yang berbeda. Hamzah Fansûrî
menyebarkan ajarannya di negeri Melayu, sementara Mullâ Sadrâ mengembangkan
ajarannya di negeri Persia. Konteks negeri Melayu membuat Hamzah Fansûrî
871 Penjelasan tentang jenis-jenis dan posisi kopula, lihat, Jabir, Wahdah Al-Wujûd Ibn
‘Arabî Dan Filsafat Wujûd Mulla Sadrâ…, 35–38.
203
menyebarkan ajarannya melalui cara-cara yang sederhana, yakni melalui objek-objek
analogi yang mudah dipahami masyarakat Melayu pada masa itu. Sementara konteks
Persia yang telah memiliki khazanah yang luas mencakup perkembangan filsafat
Aristotelian, menjadikan Mullâ Sadrâ menyebarkan ajaran yang sintesis dengan
mendialogkannya dengan berbagai khazanah keilmuan, termasuk filsafat
Aristotelian.
Berbeda dengan Persia, masyarakat Melayu memang memiliki tradisi
pembelajaran keilmuan yang luas, seperti tasawuf dan teologi. Tetapi di negeri
Melayu, diskursus filsafat Aristotelian kurang berkembang. Diskursus filosofis
memang memiliki tradisi, tetapi yang berkembang adalah corak Neoplatonisme yang
ditransmisi ke dalam ajaran tasawuf filosofis872. Diskursus tersebut telah dikenal
sejak Kerajaan Samudra Pasai. Menariknya, sekalipun tidak benar-benar lepas dari
tradisi Wujudiah, Hamzah Fansûrî tetap menggunakan cara-cara yang membuat
ajarannya mudah dipahami.
Namun, Wujudiah Hamzah Fansûrî dianggap ajaran yang rumit. Padahal
sebenarnya, ajaran itu yang sebagian besarnya dihadirkan dalam bentuk metafora,
bukan untuk menjadikan karyanya sebagai sesuatu yang sulit dipahami, tetapi malah
untuk membuat Wujudiah benar-benar dekat dengan masyarakat melalui analogi-
analogi yang dekat dengan keseharian semua masyarakat, seperti tanah, air, kayu,
buah, cahaya, batu, sungai, cermin, besi, dan sebagainya. Dalam pendekatan melalui
analogi, tidak diperlukan suatu epistemologi burhanî yang sistematis sebagaimana
berlaku dalam filsafat. Namun demikian, sistem epistemologi filsafat memiliki
keunikan pada bidang tertentu, yakni memberikan kepuasan atas objek yang dikaji
karena kejelasannya dan memuaskan nalar. Dalam sistem analogi, terdapat tantangan,
yakni ketika sifat dasar dari instrumen analogi tidak dapat diketahui, otomatis
menggagalkan pemahaman atas maksud sesuatu yang ingin dianalogikan. Namun,
bila telah mengetahui sifat dasar objek analogi, ajaran Wujudiah Hamzah Fansûrî
dapat mudah dipahami.
Seperti dalam analogi tanah sebagai wujûd dan segala perabotan yang dibentuk
darinya, seperti kendi, buyung, periuk, tempat, dan bejana sebagai analogi makhluk-
makhluk, itu sangat mudah dilakukan masyarakat sehingga sangat mudah dipahami
analoginya. Memproduksi perabotan sederhana untuk dan oleh masyarakat umum
memang dilakukan secara individual dengan jumlah yang dibutuhkan saja. Tidak
seperti produksi perabotan hari ini yang diproduksi oleh pihak tertentu dalam jumlah
yang banyak untuk didistribusikan kepada masyarakat luar. Tidak pula produksi
perabotan tanah pada masa itu seperti produksi batu-bata dari tanah liat hari ini yang
juga diproduksi dengan jumlah yang sangat banyak oleh sekelompok orang, lalu
didistribusikan kepada banyak orang873.
872 Humaidi, “Mystical-Metaphysics: The Type of Islamic Philosophy in Nusantara in
the 17th-18th Century,” Jurnal Ushuluddin 27, no. 1 (July 30, 2019): 90. 873 Semakin modern sebuah zaman, maka hegemoni alat produksi semakin
tersentralisasi. Semmy Tyar Armandha, “Komunitas Ekonomi Asean Dan Meningkatnya Arti
Penting ADMM: Sebuah Analisis Ekonomi Politik Keamanan,” Jurnal Pertahanan & Bela
Negara 4, no. 3 (August 8, 2018), http://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/338.
204
Hamzah Fansûrî yang mengajarkan Wujudiah yang dalam ajaran tersebut
wujûd dilihat sebagai satu kesatuan mutlak, sementara dalam kehidupan kita
menemukan banyak wujûd, melahirkan kebingungan dalam memahami ajaran
tersebut. Akan tetapi, Hamzah Fansûrî punya jalan keluar untuk membuat ajarannya
itu menjadi sangat sederhana dan mudah sekali untuk dipahami secara baik oleh siapa
saja, yaitu dengan analogi tanah dan perabotan-perabota, seperti kendi, buyung,
periuk, tempat, dan bejana. Sementara Mullâ Sadrâ merumuskan ajarannya dengan
sangat rumit dan penuh ambigu. Bila ajaran Hamzah Fansûrî dapat dipahami hanya
dengan memahami sifat dasar analoginya, ajaran Mullâ Sadrâ hanya memungkinkan
untuk dipahami apabila telah memahami berbagai prinsip ajaran pemikiran
sebelumnya, seperti Wujudiah Ibn ‘Arabi yang rumit, al-Hikmah al-Isyrâqiyyah, dan
al-Hikmah al-Masyâ'iyyah.
Sebagaimana tanah dan perabotan-perabotan dari tanah, dalam analogi catur
juga Hamzah Fansûrî telah membuat ajaran Wujudiah yang sangat rumit menjadi
sangat mudah dipahami. Ajaran Hamzah Fansûrî hanya terkesan rumit dan
membingungkan ketika telah dipengaruhi stigma yang menyatakan bahwa ajaran
Hamzah Fansûrî itu berat. Padahal, tidak hanya ajaran tasawuf Hamzah Fansûrî,
hampir semua ajaran itu tidak diusahakan menjadi berat oleh pengarangnya.
Sebaliknya, pengarang berusaha supaya ajarannya itu dipahami pembaca karena
memang tujuan sebuah ajaran untuk menyampaikan sebuah pesan. Mustahil pesan
yang disampaikan ingin tidak diketahui. Demikian juga Mullâ Sadrâ yang meskipun
ajarannya dianggap rumit dan membutuhkan berbagai bekal keilmuan dalam
khazanah pemikiran Islam, ajarannya itu sesuai dengan konteks masyarakatnya yang
memiliki lingkungan filsafat yang diestimasikan mudah memahami ajaran Mullâ
Sadrâ.
Melalui skema estimasi kesederhanaan sebuah ajaran maka ekspektasi untuk
mendekati ajaran Hamzah Fansûrî menjadi lebih sederhana menjadi mungkin.
Dengan demikian, pembaca menjadi tidak membawa beban sebelum membaca suatu
ajaran sehingga tidak dihantui rasa takut ketika mempelajarinya seperti dalam karya-
karya Hamzah Fansûrî yang dianggap sangat berat dan membuat orang enggan
mendekatinya. Padahal, karya-karya Hamzah Fansûrî disajikan dalam bentuk
sastrawi yang amat puitis dan menggunakan analogi-analogi yang sangat sederhana.
Hamzah Fansûrî sangat mampu dalam menyederhanakan tema yang oleh sufi
sebelumnya dijelaskan dengan sangat rumit sehingga tema itu dianggap memang
sangat berat dan tidak mudah dipahami. Kajian interdisipliner yang digunakan Ibn
‘Arabî dalam menjelaskan ajaran Wujudiah membuat ajaran tersebut menjadi sangat
rumit. Perlu menguasai berbagai disiplin keilmuan, minimal ilmu-ilmu rasional,
seperti matematika, filsafat, dan logika untuk dapat memahami ajaran-ajaran Ibn
‘Arabî, khususnya salah satu karya terpentingnya, al-Futûhât al-Makkiyah’874.
Di tangan Hamzah Fansûrî, ajaran Wujudiah menjadi sangat sederhana. Dari
analogi-analogi sekunder seperti dalam menjelaskan tentang Ilmu Tuhan, Hamzah
Fansûrî mengambil analogi Ibn ‘Arabî tentang biji875. Ilmu Tuhan telah eksis dan
874 Chittick, The Self-Disclosure of God: Principles of Ibn Al-’Arabi’s Cosmology…,
x. 875 Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri…, 138.
205
bersifat tetap. Kandungan ilmu Tuhan itu seperti biji. Di dalamnya telah terkandung
keseluruhan buah. Dalam biji telah terkandung batang, daun, akar, cabang, ranting,
dan buah. Memang analogi itu dipinjam oleh Hamzah Fansûrî dari Ibn ‘Arabî. Akan
tetapi, Ibn ‘Arabî sendiri menjelaskan tentang ilmu Tuhan secara panjang lebar
dengan melibatkan berbagai disiplin keilmuan. Hal ini dilakukan Ibn ‘Arabî karena
dia hidup di jantung kebudayaan dan peradaban Islam sehingga harus berdialog
dengan ragam pemikiran besar. Misalnya dalam membahas tentang ilmu Tuhan,
selain dengan menggunakan analogi, Ibn ‘Arabî perlu menanggapi gagasan besar
mutakallimîn, seperti Abû Hamid al-Ghazalî dan gagasan besar filosof, seperti Ibn
Sînâ. Demikian juga Mullâ Sadrâ yang menyampaikan ajarannya dengan berdialog
dengan berbagai khazanah filsafat secara luas, mendalam, dan panjang lebar. Itu
memungkinkan dilakukan untuk konteks masyarakat ilmiah Persia pada masa
tersebut.
Sementara di dunia Melayu, meskipun perdebatan tentang ilmu Tuhan telah
terjadi sejak kemajuan Kesultanan Samudra Pasai, Hamzah Fansûrî memilih
merespons persoalan tersebut dengan analogi yang signifikan sehingga tidak perlu
melibatkan diri dalam perdebatan yang panjang lebar agar tidak membuat persoalan
tersebut menjadi makin rumit876. Perdebatan yang terjadi di Indonesia hanya antara
mutakallimîn dan sufi falsafi. Problem filsafat murni tidak terjadi di Indonesia877.
2. Perbedaan Pemahaman atas Status Kemajemukan Realitas Eksternal
Wujudiah Hamzah Fansûrî dan filsafat Mullâ Sadrâ menolak sikap skeptis
yang berpandangan bahwa alam semesta hanyalah proyeksi mental878. Dalam
pandangan kedua pemikir ini, realitas eksternal adalah kehadiran wujûd yang tunggal.
Sementara kemajemukan secara ontologis diterima sebagai proyeksi mental dari
realitas eksternal yang tunggal. Namun secara epistemologis, Wujudiah Hamzah
Fansûrî dan filsafat Mullâ Sadrâ memiliki bahasa teknis masing-masing dalam
menjelaskan kehadiran kemajemukan879. Perbedaan dimensi epistemologis ini sangat
menentukan perbedaan pandangan atas status kemajemukan pada realitas eksternal.
Pemikiran Mullâ Sadrâ sebagai bagian dari disiplin filsafat, antara lain,
menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbasis pada argumentasi yang sesuai
dengan kaidah pembuktian filsafat. Mullâ Sadrâ menawarkan bahwa kemajemukan
adalah proyeksi inteleksi yang merupakan bagian dari daya jiwa. Daya ini juga hadir
dalam bentuk pengindraan (tajribî) sebagai langkah awal persepsi. Lalu, intelek
(burhânî) menganalisis realitas eksternal dan membaginya menjadi substansi dan
aksiden untuk membentuk identitas tiap-tiap entitas. Tiap-tiap entitas oleh intelek
dibedakan menjadi dua akspek, yakni mâhiyâh dan wujûd. Wujûd adalah dasar
876 Di Samudra Pasai, diskursus tasawuf falsafi yang diwakili Syaikh Abdul Jalil dan
Maharaja Bakoy Ahmad Permala dan teologi yang diwakili ulama arus utama. Tempaknya
perdebatan ini sangat bernuansa politis untuk meneguhkan dominasi raja di Pasai. Lihat,
Hasjmy, Ruba’i Hamzah Fansûrî, 1. 877 Humaidi, “Mystical-Metaphysics: The Type of Islamic Philosophy in Nusantara in
the 17th-18th Century,”…, 90. 878 Gharawiyan, Pengantar Memahami Buku Daras Filsafat Islam…, 57. 879 Thabâthabâ’î, Bidâyah al-Ḥikmah…, 1.
206
realitas yang tunggal, sementara mâhiyâh adalah limitasi bagi wujûd yang berguna
sebagai media pengenalan wujûd bagi intelek880. Pengenalan atas wujûd adalah
karena kecenderungan wujûd yang satu sekaligus beragam.
Adapun dalam Wujudiah Hamzah Fansûrî, kemajemukan realitas eksternal
adalah berasal dari pancaran bayangan Haqq Ta’ala yang mana manusia sebagai
cerminnya881. Dalam hal ini, baik Wujudiah Hamzah Fansûrî yang menganalogikan
manusia dengan cermin maupun Mullâ Sadrâ yang mengandalkan inteleksi, sama-
sama sepakat bahwa kemajemukan diproyeksikan oleh manusia. Dalam hal ini, Mullâ
Sadrâ menggambarkan sistem kerja inteleksi secara sangat sistematis. Namun
demikian, Mullâ Sadrâ mengakui bahwa daya inteleksi merupakan bagian dari
rangkaian daya jiwa yang mana jiwa tersebut adalah bagian dari gradasi wujûd882.
Dalam Wujudiah Hamzah Fansûrî, aktualitas alam semesta yang majemuk
adalah aktualitas Ilmu Tuhan yang terkandung dalam ‘‘ayân al-tsabîtah. Akan tetapi,
Mullâ Sadrâ tidak dengan tegas menyatakan bahwa alam semesta adalah aktualitas
dari kecenderungan Sifat ‘Ilmû dari Tuhan883. Meskipun demikian, Mullâ Sadrâ
menyatakan bahwa Tuhan mengetahui perkara-perkara universal dan perkara-perkara
partikular yang tentunya maksud partikular dalam hal ini adalah kemajemukan alam
semesta. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Tuhan mengetahui perkara
partikular melalui pengetahuan manusia, seperti melalui indra (tajribî), intelek
(burhânî), presentasi (‘irfânî), dan sebagainya karena bentuk-bentuk pengetahuan itu
adalah daya jiwa. Sementara jiwa merupakan bagian dari wujûd. Adapun dalam hal
ini, Wujudiah Hamzah Fansûrî dengan tegas mengatakan bahwa manusia sama sekali
tidak memiliki daya, kecuali daya Tuhan sehingga wujûd, kehidupan, ilmu, dan
kehendak yang dimiliki manusia adalah sepenuhnya dari Tuhan. Pandangan
Wujudiah Hamzah Fansûrî dalam hal ini dapat dibanding dengan konsep imkân al-
faqr dalam Mullâ Sadrâ 884 sebagaimana status buah catur di hadapan pemain catur
dan status besi di hadapan pandai besi885.
Secara ontologis realitas eksternal yang majemuk diakui sebagai realitas yang
nyata, baik oleh Wujudiah Hamzah Fansûrî maupun Mullâ Sadrâ sehingga
hubungannya dapat digolongkan ekuivalen, tetapi secara epistemologis, sebagai
konsekuensi Wujudiah Hamzah Fansûrî yang berlandaskan pada metode irfânî dan
Mullâ Sadrâ yang sangat melibatkan burhânî maka hubungan keduanya tidak dapat
dikategorikan ekuivalen. Secara epistemologis, kemajemukan dalam Mullâ Sadrâ
dapat dikatakan riil karena status mental itu riil sebagai bagian dari status wujûd yang
880 Rahman, The Philosophy of Mullâ Sadrâ (Sadr Al-Din Al-Shirazi)…, 215. 881 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,”…, 282. 882 Kerwanto, “Manusia Dan Kesempurnaannya (Telaah Psikologi Transendental
Mullā Shadrā).”…, 133. 883 Fazlur Rahman yang mengkaji pemikiran Mullâ Sadrâ mengklaim bahwa
munculnya gradasi adalah karena perbedaan kecenderungan dalam wujûd yang tunggal yang
dimaknai sebagai Sifat-sifat Tuhan. Lihat, Rahman, The Philosophy of Mullâ Sadrâ (Sadr Al-
Din Al-Shirazi)…, 37–38. 884 Jabir, Wahdah Al-Wujûd Ibn ‘Arabî Dan Filsafat Wujûd Mulla Sadrâ…, 85. 885 Ali Arshad Riahi, “A Study of the Effect of Human Soul on External Objects :
Between Copenhagen School And Mullâ Sadrâ,” Kanz Philosophia : A Journal for Islamic
Philosophy and Mysticism (2015)…, 19.
207
satu dalam gradasinya. Karena itu, kandungan dalam realitas mental itu juga
merupakan sesuatu yang riil, termasuk prinsip-prinsip identitas dan nonkontradiksi
sebagai prasyarat kemajemukan. Hal ini dapat diperkuat dengan penerimaan Mullâ
Sadrâ atas objek persepsi sebagai kesatuan dengan subjek. Objek yang diketahui itu
adalah satu sekaligus bergradasi. Keniscayaan kemajemukan dalam epistemologi
Mullâ Sadrâ merupakan konsekuensi atau konsistensi dari prinsip taskîk al-wujûd
dalam ontologinya886.
Sementara dalam Wujudiah Hamzah Fansûrî, sekalipun menerima objek
pengetahuan sebagai sesuatu yang nyata pada dirinya (think by it self), secara
epistemologis kemajemukan ekstensi tidak dapat diterima, bukan hanya karena istilah
yang digunakan adalah wahmî, melainkan karena Wujudiah Hamzah Fansûrî secara
prinsipiel tidak menerima gradasi wujûd sehingga tidak memiliki alasan menerima
kemajemukan. Memang Wahdah wujûd menerima perbedaan antara kendi, buyung,
periuk, tempat, dan bejana. Juga menerima perbedaan antara raja, menteri, gajah,
kuda, benteng, dan bidak. Namun, perbedaan-perbedaan tersebut diakui hanya
sebagai majasi, bukan secara hakiki. Hal ini karena, “Sungguhpun pada zahirnya ada
ia berwujûd, tetapi wahmî juga, bukan wujûd haqiqi; seperti bayang-bayang dalam
chermin, rupanya ada hakikatnya tiada.”887 Seperti raja, menteri, gajah, kuda,
benteng, dan bidak, hanya diterima sebagai satu kesatuan, yakni buah catur.
Demikian juga kendi, buyung, periuk, tempat, dan bejana hanya diterima sebagai satu
kesatuan, yakni tanah. Kemajemukannya hanya majasi sehingga persamaannya
hanya pada status ontologis, yakni realitas tajribî itu satu kesatuan wujûd. Akan
tetapi, secara epistemologis Mullâ Sadrâ menerima sekaligus kemajemukan, namun
Wujudiah Hamzah Fansûrî tidak menerima kemajemukan.
Wujudiah Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ sama-sama menerima bahwa alam
materi seperti jasad bersifat temporer dalam waktu, sementara jiwa bersifat kekal.
Hamzah Fansûrî mengakui bahwa meskipun alam materi bersifat baharu dalam
aktualitasnya, menurutnya alam rohani bersifat kekal. Demikian juga Mullâ Sadrâ
mengatakan bahwa alam materi hanyalah bagian dari perjalanan jiwa yang sangat
panjang. Materi bisa bersifat baharu, tetapi jiwa bersifat kekal888.
Wujudiah Hamzah Fansûrî dan filsafat Mullâ Sadrâ sama-sama menerima
kemajemukan itu berada dalam ranah mental. Bagi Mullâ Sadrâ, kemajemukan
realitas eksternal adalah karena gradasi dari satu wujûd. Sementara bagi Wujudiah
Hamzah Fansûrî, kemajemukan itu adalah produksi dari jiwa. Sebenarnya, keduanya
sepakat bahwa kemajemukan itu adalah produksi dari daya jiwa. Baik dalam
Wujudiah Hamzah Fansûrî maupun filsafat Mullâ Sadrâ, kemajemukan itu diterima
sebagai hal-hal yang eksis pada dirinya (thing by it self). Akan tetapi, karena masing-
masing berangkat dari pendekatan yang berbeda, penjelasan status kemajemukan itu
menjadi berbeda. Dalam Wujudiah Hamzah Fansûrî, kemajemukan itu dianalogikan
dengan bayangan.
Dalam hal ini, menjadi penting memperjelas bayangan yang dibuat Hamzah
Fansûrî. Bagi Hamzah Fansûrî yang menganut kesatuan wujûd, wujûd bayangan yang
886 Rahman, The Philosophy of Mullâ Sadrâ (Sadr Al-Din Al-Shirazi)…, 34. 887 Fansûrî, “Asrâr Al-‘Arifîn,” …, 282. 888 Mullâ Sadrâ, Al-Syawâhid al-Rubûbiyyah fî al-Manâhij al-Sulûkiyyah …, 310.
208
majemuk, pada diri sang bayangan adalah eksistensi yang tidak terpisah dengan
empunya bayangan. Sang bayangan menjadi wahmî adalah pada atributnya yang
dibentuk oleh inteleksi, bukan pada eksistensinya karena eksistensi bagi bayangan
adalah nyata. Eksistensi tersebut adalah satu dengan empunya bayangan. Dalam
ajaran Wujudiah yang dipegang Hamzah Fansûrî, ketundukan bayangan terhadap
empunya bayangan adalah konsekuensi dari satu wujûd yang hanya berbeda dalam
sisi wahmî (inteleksi). Sementara wahmî yang dimaksud bukan ketiadaan, tetapi
adalah suatu daya inteleksi yang mana intelek merupakan bagian dari daya jiwa.
Sementara jiwa adalah bagian dari wujûd yang satu889.
Wujudiah Hamzah Fansûrî menerima eksistensi realitas eksternal sebagai hal
yang memiliki wujûd pada dirinya, yang mana dalam hal ini pandangan tersebut
ekuivalen atau identik dengan Mullâ Sadrâ yang juga menerima kemajemukan
realitas eksternal sebagai yang nyata. Sementara meskipun menerima eksistensi
realitas eksternal, Wujudiah Hamzah Fansûrî tidak menerima kemajemukan sehingga
dalam kasus kemajemukan realitas eksternal, hubungan antara Wujudiah Hamzah
Fansûrî dan Mullâ Sadrâ adalah nonekuivalen atau berbeda. Hal ini karena Hamzah
Fansûrî tidak menerima kemajemukan realitas eksternal, sementara Mullâ Sadrâ
menerimanya.
3. Multiperspektif Varian dan Sasaran Kritikan
Perbedaan penting lainnya antara ajaran Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ
adalah nasib ajaran mereka masing-masing. Ajaran Mullâ Sadrâ ditolak dalam waktu
tidak lama. Selanjutnya, setelah dipelajari secara mendalam dan menyeluruh, ajaran
tersebut diterima dengan baik. Awalnya, ajaran Mullâ Sadrâ dicurigai bertentangan
dengan prinsip-prinsip mistisme khas Persia. Namun ternyata, Mullâ Sadrâ secara
keseluruhan dalam ajarannya tidak bertentangan dan bahkan dalam penafsiran
tertentu dapat dicari kemiripannya dengan tradisi mistisme Persia sebelumnya.
Ajaran Mullâ Sadrâ menjadi diterima dengan baik oleh kalangan intelektual di sana.
Di antara alasannya karena pada masa itu, para pemikir sedang berusaha merumuskan
karya yang mampu menyintesis berbagai varian pemikiran. Kehadiran Mullâ Sadrâ
dianggap mampu mewujudkan ekspektasi itu.
Sementara itu, ajaran Hamzah Fansûrî sebelum kedatangan Nûr al-Dîn al-
Ranîrî diterima dengan baik. Ajaran tersebut memang dirumuskan dengan sangat
sesuai bagi masyarakat Melayu. Ajaran Wujudiah yang sebelumnya dikenal sangat
rumit dihadirkan dalam bahasa yang indah dan menggunakan analogi yang mudah
dipahami masyarakat. Sayangnya, ajaran Hamzah Fansûrî diklaim sesat oleh Nûr al-
Dîn al-Ranîrî. Meskipun sempat mendapatkan pembelaan dari Sayf al-Rizâl,
Wujudiah Hamzah Fansûrî tetap menjadi asing bagi masyarakat, bahkan hingga kini.
Dalam Tibyan dan Hujjat, Nûr al-Dîn al-Ranîrî memberikan porsi besar untuk
menunjukkan hal-hal yang dianggapnya penuh ketimpangan di dalam ajaran
Wujudiah Hamzah Fansûrî. Dalam Tibyan, Nûr al-Dîn al-Ranîrî tidak menyebutkan
ajaran Wujudiah Ibn ‘Arabî itu sesat. Bahkan di dalam Hujjat, Nûr al-Dîn al-Ranîrî
889 Gambaran bayangan menurut ‘Abd al-Ra’uf al-Sinkilî dapat dilihat pada pengantar
Tanbih al-Masyi. Lihat, Fathurahman, Tanbih Al-Masyi: Menyoal Wahdatul Wujud: Kasus
Abdurrauf Singkel Di Aceh Abad 17, 1.
209
memuji Ibn ‘Arabî sebagai sufi yang menganut ajaran yang benar. Ajaran Hamzah
Fansûrî dikritik secara mendalam. Ajaran Hamzah Fansûrî ditegaskan benar-benar
sesat. Padahal, Hamzah Fansûrî dengan jelas merupakan pengikut ajaran Wujudiah
sebagaimana Ibn ‘Arabî. Bahkan, memahami Wujudiah Hamzah Fansûrî lebih
sederhana dan tidak serumit pendekatan Ibn ‘Arabî. Penentangan itu terjadi, antara
lain, karena Wujudiah yang diajarkan Hamzah Fansûrî menggunakan analogi-analogi
yang berpotensi mengarahkan pemahaman mirip kepada ajaran reinkarnasi milik
Tanasukhiyyah, Jawhar Basith dalam filsafat, Wathaniyah, Barahimah, dan
Hululiyyah.
Dikatakan Nûr al-Dîn al-Ranîrî, bahwa Hamzah Fansûrî dan Shams al-Dîn al-
Sumatranî berpaham demikian. Dikatakan juga ajaran ini meyakini kejadian (takwin)
dengan yang menjadikan (mukawwin), dan aktivitas (tafa'ul) pengaktif (mufa'al)
adalah satu. Di samping itu, Jahamiyyah Zanadiqiyyah yang meyakini kekekalan
alam mirip dengan iktikad Hamzah Fansûrî dan Shams al-Dîn al-Sumatranî karena
bertentangan dengan Al-Qur’an yang menyatakan bahwa Allah-lah yang menjadikan
segala sesuatu (QS. 13: 16). Ditegaskan Nûr al-Dîn al-Ranîrî, dalam pandangan Ahlu
Sunnah wal Jama’ah, siapa yang meyakini ma'lum, maksudnya, objek pengetahuan
Tuhan itu ada sesuatu maka dia itu kafir. Dikatakan mereka adalah yang meyakini
eksistensi materi primer dan a'yan tsabitah.
Nûr al-Dîn al-Ranîrî mengatakan, Hamzah Fansûrî dalam al-Muntahî
meyakini makna hadis qudsi, “Siapa kenal diri, maka telah kenal Rabb-nya.” Bahwa
dirinya dan sekalian alam dalam ilmu Allah seumpama sekalian bagian pohon telah
lengkap dalam biji. Maka dari itu, keluarlah alam dari ilmu Allah seperti keluarnya
batang, daun, dan buah dari biji. Dikatakan paham demikian adalah kufur.890 Menurut
Nûr al-Dîn al-Ranîrî pula, Hamzah Fansûrî tidak membenarkan menyifatkan melihat
Haqq Ta’ala seperti kain basah dan air karena air dan kain berbeda, tetapi harus
seperti laut dan ombak karena laut adalah satu dengan ombak sehingga makhluk
dengan Allah satu. Matahari, cahaya matahari, dan panas matahari, meski nama dan
rupanya tiga, hakikatnya satu. Nûr al-Dîn al-Ranîrî mengatakan paham demikian
seperti paham falasifah atau paham Nasrani yang meyakini wujûd Bapa, wujud Anak,
dan dan wujûd Ibu adalah tiga nama yang hakikatnya satu wujûd. Dalam pemahaman
Hamzah Fansûrî, ''Siapa kenal dirinya ...'' bukan mengenal jantung, paru-paru, kaki
atau tangan, dimaknai Nûr al-Dîn al-Ranîrî adalah bermaksud mengiktikadkan wujud
makhluk dan wujûd Tuhan adalah Esa. Padahal, Wujudiah Hamzah Fansûrî hanya
menerima satu wujûd, yakni Haqq Ta’ala dan selain-Nya adalah bayangan (wahmî).
Dalam penilaian Nûr al-Dîn al-Ranîrî, Hamzah Fansûrî mengatakan keadaan
makhluk berawal dengan keadaan Tuhan dan melihat Tuhan dengan penglihatan-
Nya. Paham demikian menjadikan wujûd dan sifat makhluk yang baharu bersatu
dengan wujûd dan sifat Qadim Tuhan. Hamzah Fansûrî meyakini wujûd itu pada zahir
majemuk dan berubah-ubah karena Dia Awal dan Dia Akhir. Awal tiada ketahuan,
Akhir tiada Kesudahan; Batin tiada terjangkau, pada zat, pada sifat, pada perbuatan,
dan pada jejak (atsar), yang mana empat itu hakikatnya adalah satu. Paham tersebut
menjadikan makhluk dan Khalik bersuatu. Bagi Nûr al-Dîn al-Ranîrî, pernyataan
890 Nûr al-Dîn Al-Ranîrî, Al-Tibyan fî Ma’rifat al-Adyân, ed. Muhammad Kalam Daud
(Banda Aceh: PeNa, 2011), 168–169.
210
Hamzah Fansûrî, ''Pada zahirnya wujud makhluk, tetapi pada hakikatnya Allah,''
adalah paham ittihad. Nûr al-Dîn al-Ranîrî mengecam pandangan ittihad
sebagaimana dipegang oleh Abû Yazid al-Bistamî.
Hamzah Fansûrî disebutkan meyakini pada hakikatnya Zahir dengan mazhar
tiada bercerai. Hamzah Fansûrî meyakini ilmu pertama adalah pengetahuan terhadap
Allah. ''Adapun kesudahan-sudahan makrifat itu tatkala datanglah kepada had faqir
bahwa ialah Allah.'' Maksud Nûr al-Dîn al-Ranîrî, paham penganalogian makhluk
dengan Haqq dengan bertiup angin ombak timbul, berhenti angin, ombak kembali,
adalah kufur karena kesalahannya telah nyata891.
Nûr al-Dîn al-Ranîrî mengecam keyakinan yang menganalogikan Khaliq
seperti biji dengan pohon kayu di dalamnya sebagai paham zindik yang menyebabkan
kekufuran. Disimpulkan bahwa paham demikian meyakini dua zahir kelihatan,
namun hakikatnya satu. Paham demikian dianggap sama dengan paham Abû Mansûr
al-Hallaj yang menyatakan zatnya tiada dilihat lagi, kefakiran adalah tiada suatu apa
pun baginya. Hamzah Fansûrî dikatakan telah menyerukan, ''Jika tiada menerima
kufur, maka tiada bertemu dengan kufur.''
Maksud Hamzah Fansûrî menganalogikan makhluk sudah terkandung dalam
Ilmu Allah sebagaimana keseluruhan pohon sudah terkandung dalam biji adalah
untuk menjelaskan bahwa eksistensi alam bukan dari ketiadaan, namun berasal dari
eksistensi juga sekalipun keberadaannya belum aktual. Statusnya dalam filsafat
adalah seperti materi primer. Statusnya adalah mukmin al-wujûd. Mumkin al-wujûd
tidak dikategorikan wujud karena belum aktual, namun bukan merupakan ketiadaan
karena berpotensi mengada. Ketiadaan tidak memiliki potensi untuk mengada.
Keadaan ini dianalogikan seperti dalam sebuah biji yang telah terkandung padanya
keseluruhan pohon dari akar, batang, cabang, ranting, hingga buahnya.892
Hamzah Fansûrî tidak menginginkan penyifatan hubungan Tuhan dengan
makhluk seperti kain basah karena air dan kain itu berbeda. Hamzah Fansûrî tidak
beriktikad wujûd itu majemuk, tetapi tunggal. Kepercayaan wujûd itu majemuk dalam
pandangan sufi Wujudiah adalah syirik. Nûr al-Dîn al-Ranîrî sendiri dalam Tibyan
telah menyatakan bahwa iktikad yang benar itu adalah meyakini hanya wujûd Allah
yang nyata, sementara wujud yang lain itu hanya seperti bayangan di dalam cermin.
Dalam hal ini, baik Hamzah Fansûrî maupun Hamzah Fansûrî berpandangan mirip.
Masalahnya adalah Nûr al-Dîn al-Ranîrî tidak menginginkan analogi hubungan
Tuhan dan makhluk seperti hubungan laut dan ombak. Hal ini karena mengesankan
wujûd makhluk menyatu dengan wujud Tuhan. Padahal dalam tulisan-tulisannya,
berulang kali Hamzah Fansûrî menegaskan bahwa selain Haqq Ta’ala, wujudnya
majasi atau wahmî. Mengenal diri dalam pandangan Hamzah Fansûrî bukan
mengenal organ tertentu, melainkan mengenal wujûd. Di sana, ditemukan wujûd itu
hanya satu. Sementara segala objek material yang terindrai itu bukan wujudnya,
melainkan aksiden-aksidennya. Wujûd itu satu. Dia adalah Awal dan Akhir.893 Dia
hadir pada setiap realitas. Akan tetapi, yang dimaksud dengan realitas adalah wujûd
-nya, bukan modus wujûd, yakni aksiden-aksiden yang terindrai.
891 Nûr al-Dîn Al-Ranîrî, Al-Tibyan fî Ma’rifat al-Adyân…,172. 892 Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri…, 132. 893 Doorenbos, De Gefchriften van Hamzah Pansoeri…, 162.
211
Dalam hal ini, secara umum Nûr al-Dîn al-Ranîrî menentang Wujudiah
Hamzah Fansûrî karena analogi-analogi yang digunakan. Analogi-analogi, seperti
matahari dan cahayanya, laut dan ombak, serta buah dan biji. Dalam hal ini,
penyasaran Nûr al-Dîn al-Ranîrî atas analogi-analogi dalam Asrâr merupakan bagian
dari kecemerlangan Nûr al-Dîn al-Ranîrî untuk menemukan inti gagasan Hamzah
Fansûrî. Hal lain yang sangat mendukung alasan utama penolakan Nûr al-Dîn al-
Ranîrî atas Wujudiah Hamzah Fansûrî adalah karena sufi Melayu itu tidak hanya
menyerap ajaran Wujudiah yang dianggap lurus, seperti Ibn ‘Arabî, tetapi juga
menyerap ajaran Wujudiah yang dianggap sesat oleh Nûr al-Dîn al-Ranîrî, seperti
ajaran Abû Mansûr al-Hallaj dan Abû Yazid al-Bistamî. Namun, Nûr al-Dîn al-Ranîrî
tetap menganggap Ibn ‘Arabî sebagai sufi Wujudiah yang lurus (muwahid) meskipun
Ibn ‘Arabî sebelumnya telah menggunakan analogi-analogi yang dianggap tidak
akurat saat digunakan Hamzah Fansûrî. Dengan kritik tajam dari Nûr al-Dîn al-Ranîrî
meskipun sempat dibela kembali oleh Sayf al-Rizâl, Mufti Aceh Darussalam dari
Minangkabau, selanjutnya ajaran Hamzah Fansûrî tetap tidak diterima secara luas.
Sementara itu, di dunia Persia, filsafat Mullâ Sadrâ mengalami nasib yang
sangat baik. Meskipun sempat dicurigai hendak melemahkan semangat al-Hikmah
al-Isyrâqiyyah yang telah terlanjur membuat kagum masyarakat Persia, ternyata
setelah dipelajari secara utuh dan mendalam, filsafat Mullâ Sadrâ diterima dengan
baik karena masih mengusung semangat mistisme khas Persia. Masyarakat Persia
sangat bangga dengan kegemilangan mistisme khas budaya mereka, termasuk al-
Hikmah al-Isyrâqiyyah. Sebab itulah, filsafat Mullâ Sadrâ itu dicurigai pada awal
kemunculannya. Namun, selanjutnya begitu diminati karena dianggap mampu
menyintesis berbagai varian pemikiran sebelumnya.
Di samping itu, filsafat Mullâ Sadrâ diterima dengan baik karena memiliki
dimensi sistem rasional bergaya Aristotelian yang didayagunakan untuk
memantapkan argumentasi mistisme. Kehadiran Mullâ Hâdî Sabzawârî yang
melakukan radikalisasi aspek mistis filsafat Mullâ Sadrâ, khususnya dalam gaya
bahasa Arab yang sangat sastrawi membuat ajaran itu makin diminati. Maka dari itu,
tak heran pada era modern filsafat Mullâ Sadrâ sangat diapresiasi dalam pemaknaan
mistisnya. Terdapat kemungkinan kecenderungan tersebut terjadi karena krisis
spiritualitas memang melanda umat manusia pada era modern894.
Hasan Zâdeh Amûlî, Sayyid Yadullah Yazdan Panah, dan Hasan Mu’allimî
menulis karya-karya tasawuf dengan mengambil aspek mistik dari filsafat Mullâ
Sadrâ. Karya-karya mereka itu bercorak sangat mistis dan jauh dari gaya filsafat
Aristotelian. Sayyid Yadullah Yazdan Panah misalnya, sebagaimana dijelaskan Nur
Jabir, menggunakan sistem tasawuf filosofis yang diistilahkan dengan ‘irfân nazârî
dalam menjelaskan filsafat Mullâ Sadrâ. Dia menggunakan sistem tiga relasi model
aspek (haitsiyyah), yaitu haitsiyah ithlaqiyyah (model aspek kemutlakan), haitsiyah
ta’liliyah (model aspek kausatif), dan haitsiyah taqyidiyah (model aspek kondisional)
yang sebenarnya itu merupakan konsep mistisme. Konsep tersebut digunakan untuk
894 Seyyed Hossein Nasr, Islam and the Plight of Modern Man (Chicago: Kazi
Publications, 2001), 18.
212
menegaskan bahwa rasionalisasi Mullâ Sadrâ dalam menjelaskan hubungan
ketunggalan dan kemajemukan bermuara pada penegasan ketunggalan wujûd.
Haitsiyah ithlaqiyyah (model aspek kemutlakan) atau relasi model aspek
absolut adalah wujûd subjek tanpa perantara, tidak memerlukan sebab dan tidak
berlaku limitasi padanya untuk eksis. “Haqq Ta’ala adalah Wujûd Sejati” karena
Haqq Ta’ala tidak membutuhkan perantara ataupun sebab untuk eksis. Haitsiyah
ta’liliyah (model aspek kausatif) adalah predikasi suatu subjek melalui perantaranya,
yang mana perantara itu adalah penyebab subjek dan merupakan wujûd sekaligus
menjadi pemberi wujûd bagi subjek. Jika perantara ini tidak ada, wujûd subjek tidak
akan memiliki wujûd. Misalnya, air yang dipanaskan melalui api. Api menjadi panas
secara hakiki, tetapi sebab panas bukan air, melainkan api. Dalam hal ini, api disebut
model aspek kausatif.
Haitsiyah taqyîdîyah (model aspek kondisional) adalah wujûd dipredikatkan
pada sebuah subjek melalui perantara karena antara subjek dan perantara tersebut
memiliki sebuah relasi. Relasi ini melekat pada perantara hanya ketika subjek
dikaitkan dengan perantara karena antara subjek dan perantara hanya berhubungan
secara kondisional atau hubungan aksiden. Misalnya, proposisi "banku itu bocor",
sebenarnya yang bocor adalah ban mobil, namun mobil dan pengendaranya punya
relasi tertentu sehingga ban dinisbahkan kepada pengendara895.
Hâitsiyah taqyîdîyah (model aspek kondisional) terbagi menjadi model aspek
hâitsiyah taqyîdîyah nafâdîyah, haitsiyah taqyidiyah indimâjiîyah, dan hâitsiyah
taqyîdîyah sya'niyah. Hâitsiyah taqyîdîyah nafâdîyah dipakai dalam analisis filsafat
Mullâ Sadrâ untuk menjelaskan hubungan wujûd dan mâhiyâh dalam prinsip
kemendasaran wujûd atas mâhiyâh896. Wujûd mengada dengan zatnya sendiri,
sementara mâhiyâh mengada dengan hâitsiyah taqyîdîyah wujûd. Misalnya, wujûd
pohon eksis dengan sendirinya, tetapi “pohon” (sebagai mâhiyâh) eksis dengan
hâitsiyah taqyîdîyah897.
Hâitsiyah taqyîdîyah indimajiyah, adalah sistem yang digunakan dalam
menganalisis pemikiran Mullâ Sadrâ dalam menjelaskan mau'qulat tsanî falsafî yang
menerangkan bahwa konsep abstrak mental yang memiliki acuan pada realitas
eksternal. Dalam prinsip kemendasaran wujûd, realitas eksternal itu adalah
sepenuhnya diisi oleh wujûd sehingga dalam abstraksi mental, konsep-konsep, seperti
sebab-akibat, wajîb-mumkîn, adalah wujûd; sementara konsep-konsep itu bukan
tambahan bagi wujûd, melainkan eksis dengan wujûd, yaitu eksis dengan hâitsiyah
taqyîdîyah indîmîjiyah. Konsep-konsep itu berada dalam wujûd dengan tidak
membuat wujûd menjadi majemuk.
Haitsiyah taqyîdîyah sya'niyah digunakan untuk menjelaskan konsep jiwa
dalam filsafat Mullâ Sadrâ yang memandang jiwa sebagai sesuatu yang sederhana
sekaligus memiliki fakultas indrawi, fakultas imajinasi, dan fakultas inteleksi.
Kehadiran jiwa dalam fakultas-fakultas itu adalah hubungan haitsiyah taqyidiyah
sya'niyah898. Meskipun dalam Wahdah al-Wujûd hanya menerima satu wujûd,
895 Jabir, Wahdah Al-Wujûd Ibn ‘Arabî Dan Filsafat Wujûd Mulla Sadrâ…, 35–38. 896 Nasr, Islamic Philosophy From Its Origin to the Present…, 68–69. 897 Jabir, Wahdah Al-Wujûd Ibn ‘Arabî Dan Filsafat Wujûd Mulla Sadrâ…, 38. 898 Jabir, Wahdah Al-Wujûd Ibn ‘Arabî Dan Filsafat Wujûd Mulla Sadrâ…, 40–42.
213
sementara selainnya bukan lokus wujûd, tetapi bukan berarti kemajemukan itu tidak
memiliki nafs al-amar. Sebenarnya, kemajemukan itu mengada dengan wujûd
melalui mode kondisi sebagaimana dijelaskan melalui hâitsiyah taqyîdîyah sya'niyah.
Maka dari itu, dalam sistem yang digunakan Sayyid Yadullah Yazdan Panah itu,
filsafat Mullâ Sadrâ menjadi sangat bernuansa mistis persis seperti Wujudiah yang
diajarkan Ibn ‘Arabî dan Hamzah Fansûrî. Dalam pemaknaan melalui perspektif ini,
sistem taskȋk al-wujûd Mullâ Sadrâ sekalipun menjadi termaknai sebagai kesatuan
wujûd yang sama seperti ajaran Wujudiah, yakni sama sekali tidak menerima
eksistensi kemajemukan.
Namun, tidak semua pemikir di sana memahami demikian. Sebagian pemikir,
seperi Sayyid Hussîn Thabattâbâ'i dan Muhammad Taqî Misbah Yazdî berusaha tidak
melibatkan aspek mistis dalam filsafat Mullâ Sadrâ dan berfokus pada filsafat
sistematis bercorak Aristotelian yang terkandung di dalamnya. Sayyid Hussîn
Thabattâbâ'i menulis dua karangan tentang filsafat Mullâ Sadrâ, yakni Bidayat al-
Hikmah dan Nihayat al-Hikmah untuk menjelaskan filsafat Mullâ Sadrâ dalam aspek
filsafat bercorak Aristotelian dalam artian sistem yang sangat rigid dan penuh
argumentasi bercorak silogisme. Demikian juga Muhammad Taqî Misbah Yazdî.
Ali Akbar Rashad menunjukkan bahwa, setidaknya terdapat tiga usaha besar
Sayyid Hussîn Thabattâbâ'i dalam usaha meradikalkan filsafat Mullâ Sadrâ menjadi
makin bercorak Peripatetik. Pertama adalah memisahkan argumen mistis (shuhûd)
dengan argumen rasional (burhân) untuk selanjutnya fokus pada argumentasi-
argumentasi rasional. Kedua, melacak akar persoalan yang dibahas Mullâ Sadrâ
dengan menunjukkan bahwa persoalan-persoalan yang menjadi fokus respons Mullâ
Sadrâ adalah persoalan-persoalan filsafat. Maksudnya adalah hendak ditunjukkan
bahwa kehadiran Mullâ Sadrâ utamanya adalah hendak berdialog dalam persoalan
filsafat. Ketiga, perbandingan dengan berbagai tradisi filsafat. Dalam hal ini, Sayyid
Hussîn Thabattâbâ'i menguatkan sistem filsafat Mullâ Sadrâ dengan mengganti
tradisi-tradisi keilmuan kuno dan menggantikannya dengan filsafat kontemporer
dalam rangka membuat sistem Aristotelian dalam filsafat Mullâ Sadrâ 899.
Sayyid Hussîn Thabattâbâ'i sangat menghindari proposisi-proposisi yang
didasarkan pada pengetahuan yang ditemukan dari pengalaman mistik. Karena dalam
filsafat Mullâ Sadrâ sendiri, argumentasi-argumentasi yang dibangun sangat sering
menjadikan pengalaman hudhûrî sebagai basis argumentasi. Dalam hal ini, Sayyid
Hussîn Thabattâbâ'i bukan hendak menolak validitas pengalaman mistik itu,
melainkan ingin berfokus pada argumentasi bercorak filsafat. Terkadang, Mullâ
Sadrâ juga mengakomodir pandangan-pandangan sains kuno, seperti fisika dan
kosmologi. Hal ini sangat dihindari Sayyid Hussîn Thabattâbâ'i. Sebagai gantinya,
dia mengintegrasikan filsafat Mullâ Sadrâ dengan argumentasi filsafat Modern dan
penemuan-penemuan sains modern. Misalnya, kosmologi masa lalu menganggap
unsur terkecil adalah air, api, dan tanah. Digantikan dengan molekul dan artikel sub-
atomik yang merupakan gagasan sains kontemporer900.
899 Ali Akbar Rashad, “Neo-Sadrian Pilosophical Discourse,” in Sadra Islamic
Philosophy Research (Tehran: SIPRIn Publication, 1999), 38–39. 900 Cipta Bakti Gama, Filsafat Jiwa: Dialektika Filsafat Islam, Dan Filsafat Barat
Kontemporer…, 104.
214
Muhammad Taqî Misbah Yazdî adalah pengikut ajaran Mullâ Sadrâ lainnya di
samping Sayyid Hussîn Thabattâbâ'i yang melihat ajaran Mullâ Sadrâ dalam sisi yang
bercorak filsafat dan menjauhkannya dari pandangan bercorak tasawuf filosofis.
Muhammad Taqî Misbah Yazdî berpandangan bahwa Mullâ Sadrâ menerima
kemajemukan realitas sebagaimana sistem taskîk al-wujûd901. Menurutnya, filsafat
Mullâ Sadrâ itu bukan kesatuan wujûd. Berpandangan bahwa kemajemukan itu riil
adanya dan tidak bertentangan dengan kesatuannya. Kemajemukan wujud itu
digambarkan seperti mata rantai yang saling berhubungan, terdapat yang lebih dahulu
dan lebih belakangan serta lebih kuat dan tidak lebih kuat, semuanya adalah satu
kesatuan sekaligus ketunggalan dalam wujûd yang mendasar.
Dengan demikian, nasib ajaran Hamzah Fansûrî dan filsafat Mullâ Sadrâ
menjadi sangat berbeda. Ajaran Hamzah Fansûrî hingga hari ini masih dianggap tabu
dan ditolak karena masih diyakini sesat oleh banyak masyarakat Indonesia.
Sementara ajaran Mullâ Sadrâ sangat diapresiasi dan sangat berkontribusi
meningkatkan semangat intelektual dan pembelajaran filsafat di negerinya. Bahkan,
perdebatan penggolongan varian dalam memahami ajaran Mullâ Sadrâ antara
pemaknaan bercorak mistik dan bercorak filsafat malah menciptakan dialektika
pemikiran yang membuat studi pemikiran di sana menjadi makin berkembang.
C. Pemaknaan Perbandingan Wujudiah Hamzah Fansûrî dan Filsafat Mullâ
Sadrâ
Relasi Wujudiah Hamzah Fansûrî dan filsafat Mullâ Sadrâ yang sama-sama
memahami wujûd sebagai univokal, mendasari realitas, dan bersifat tunggal
menjadikan dua ajaran ini paling dekat secara ontologis. Kesamaan ini bersifat
ekuivalen. Meskipun dalam tinjauan yang lebih umum dapat dikatakan filsafat Mullâ
Sadrâ sebagai disiplin filsafat Islam lebih dekat dengan al-Hikmah al-Isyrâqiyyah dan
al-Hikmah al-Masyâ'iyyah, demikian pula Wujudiah Hamzah Fansûrî sebagai bagian
ajaran tasawuf filosofis secara rumpun keilmuan dianggap lebih dekat dengan
tasawuf amal atau tasawuf akhlak, namun relasi identik univokal antara Wujudiah
Hamzah Fansûrî dan filsafat Mullâ Sadrâ menunjukkan bahwa pembagian dan
pengelompokan antardisiplin keilmuan bukan berdasarkan kesamaan aspek esensial
tiap-tiap keilmuan, yakni kefilsafatan tiap-tiap keilmuan yang mencakup aspek
ontologi, aspek epistemologi, dan aspek aksiologi. Pembagian dan pengelompokan
antardisiplin keilmuan biasanya dilakukan berdasarkan kemiripan aspek aksidennya,
khususnya dari aspek istilah dan penamaannya saja902. Pada sisi pemerimaan
ekuivokasi dan kemendasaran wujûd, Wujudiah Hamzah Fansûrî dan filsafat Mullâ
Sadrâ dapat dikatakan ekuivalen. Namun secara keseluruhan dalam pandangan
tentang wujûd, hubungan kesamaannya adalah relasi umum khusus satu sisi karena
Mullâ Sadrâ menerima kesatuan sekaligus kemajemukan wujûd.
Kesamaan penting lainnya antara Wujudiah Hamzah Fansûrî dan filsafat Mullâ
Sadrâ adalah mereka sepakat bahwa manusia harus mempersiapkan bekal untuk
mengenali diri melalui bahasa teknis yang berbeda, yakni Hamzah Fansûrî
menekankan pentingnya mengikuti jalan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat.
901 Labib, Pemikiran Filsafat Ayatullah M.T. Misbah Yadzi…, 217 902 Penjelasan antara univokal dan ekuivokal, lihat, Miswari, Filsafat Terakhir…,, 169.
215
Sementara Mullâ Sadrâ menekankan pentingnya empat perjalanan spiritual dalam
skema empat perjalanan (asfâr arba’ah)903. Kesamaan ini dapat dikatakan sebagai
relasi umum-khusus satu sisi. Hal ini karena meskipun keduanya bersamaan pada
aspek menjadikan perjalanan ke dalam diri itu bertujuan untuk menemukan
penyingkapan spiritual sehingga memperoleh ilmu hudhûrî yang merupakan sumber
pengetahuan hakiki, masing-masing menggunakan fokus pendekatan berbeda untuk
mencapai tujuan pengenalan diri itu. Pada satu sisi, Hamzah Fansûrî lebih
menekankan prosesnya melalui syariat dan tarekat. Pada sisi lain, Mullâ Sadrâ lebih
menekankan melalui penalaran rasional.
Kesamaan lainnya adalah penerimaan atas ilmu hudhûrî dan menjadikannya
sebagai sistem pengetahuan yang meyakinkan. Filsafat Mullâ Sadrâ menjadikan
hudhûrî sebagai bagian dari fondasi burhanî. Posisi irfânî adalah prasyarat bagi
validitas proposisi. Hudhûrî bagi filsafat Mullâ Sadrâ adalah alternatif bagi definisi
yang telah tertolak oleh argumentasi Syihab al-Dîn al-Suhrawardî. Maka dari itu,
filsafat Mullâ Sadrâ menjadikan hudhûrî sebagai alternatif prasyarat proposisi untuk
menggantikan definisi904. Dalam filsafat Mullâ Sadrâ, realitas dapat diketahui melalui
pendekatan tajribî, bayanî, burhânî, dan hudhûrî. Hudhûrî diandalkan untuk
mengetahui realitas sebagaimana adanya. Tajribî berguna untuk mengonfirmasi
eksistensi realitas. Wujudiah Hamzah Fansûrî dan filsafat Mullâ Sadrâ sepakat bahwa
hudhûrî adalah pendekatan untuk mengenal wujûd. Hamzah Fansûrî menggunakan
analogi dalam menjelaskan pengetahuan hudhûrî. Sementara Mullâ Sadrâ
menggunakan ilmu hudhûrî untuk memenuhi prasyarat elementer dari proposisi
untuk meneguhkan validitas burhânî. Dengan pendekatan hudhûrî, Wujudiah
Hamzah Fansûrî mengaku pengetahuan manusia dapat menjangkau ‘ayân al-tsabîtah,
yakni realitas yang menjadi perantara alam dengan maqâm Ilahi. Sementara bagi
ajaran Mullâ Sadrâ sebagai suatu perspektif ajaran filsafat, ranah tersebut tidak
dieksplorasi secara mendalam905. Tidak ada eksplorasi kondisi realitas immaterial
dalam filsafat. Filsafat hanya mengakui validitas irfânî yang dengannya Mullâ Sadrâ
menunjukkan bahwa realitas itu tunggal sekaligus bergradasi. Dalam Wujudiah,
hudhûrî menjadi pintu masuk untuk mengeksporasi realitas-realitas yang ada dalam
berbagai maqâmat alam immaterial hingga spekulasi tentang kondisi-kondisi realitas
Ilahiah yang mana oleh Hamzah Fansûrî dijelaskan melalui analogi. Sementara dalam
ajaran Mullâ Sadrâ, hudhûrî dijadikan titik tolak dalam kegiatan berfilsafat. Bagi
Wujudiah Hamzah Fansûrî, hudhûrî adalah keseluruhan dari epistemologinya.
Sementara metode lainnya hanya dijadikan bagian-bagian aksidental yang bertujuan
mengukuhkan hudhûrî. Sementara bagi Mullâ Sadrâ, hudhûrî diterima sebagai bagian
dari metodenya untuk mengukuhkan burhânî. Karena itu, hubungan kesamaan
Wujudiah Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ tentang posisi ‘irfânî tergolong relasi
umum dan khusus mutlak906.
Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ juga sama-sama menerima eksistensi alam
potensial. Hamzah Fansûrî mengistilahkannya dengan ‘ayan tsabiytah, rûh idhafî,
903 Sadrâ, al-Hikmah al-Muta’âliyah fî al-Asfâr al-‘Aqliyyah al-Arba’ah Vol. I..,, 39 904 Al-Mandary, Menuju Kesempurnaan: Pengantar Pemikiran Mullâ Sadrâ…, 204. 905 Nasution, Filsafat Ilmu Pengetahuan…, 87. 906 Skema tersebut, terdaapat dalam: Fadli, Logika Praktis, 37–38.
216
dan isti’dad aslȋ. Sementara Mullâ Sadrâ juga menerima hal yang sama dengan
menggunakan istilah materi primer (hayûlâ). Penerimaan mereka atas eksistensi alam
potensial meniscayakan pandangan bahwa aktualitas alam itu berasal dari
keberadaan, bukan ketiadaan. Hal ini karena secara logika, ketiadaan mustahil dapat
menghasilkan keberadaan. Eksistensi alam potensial menjadi kajian yang mendalam
dalam Wujudiah Hamzah Fansûrî. Keunikan filsafat dan tasawuf filosofis adalah
penerimaan mereka atas eksistensi alam potensial. Dalam hal ini, penerimaan
Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ atas eksistensi alam potensial dapat disebut
ekuivalen.
Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ sepakat bahwa kefakiran makhluk atas
Khalik adalah kebergantungan wujud. Hamzah Fansûrî menjelaskan kebergantungan
itu seperti bergantungnya besi kepada tukang besi. Tukang besi memiiki kehendak
mutlak atas besi. Sementara besi sendiri sama sekali tidak memiliki daya. Sementara
Mullâ Sadrâ menjelaskan kebergantungan mutlak makhluk atas Khalik dengan
menggunakan istilah kefakiran akibat dalam kausalitas (illiyah). Meskipun
menggunakan pendekatan istilah teknis yang berbeda, keduanya sepakat bahwa
makhluk bergantung mutlak kepada Khalik. Dalam hal ini, persamaan kedua pemikir
ini dalam mengakui kefakiran makhluk atas Khalik juga dapat dikatakan ekuivalen.
Gambar 2. Orientasi relasi
Pemikiran
Hamzah Fansûrî
Titik temu pemikiran
Hamzah Fansûrî dan
Mullâ Sadrâ
Pemikiran
Mullâ Sadrâ
Gambar 3. Persamaan pemikiran Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ
No. Unit Relasi Jenis
Persamaan Argumentasi Gambar
Relasi
1 Ekuivalen Univokasi dan
Kemendasaran
Wujûd
Hamzah Fansûrî dan
Mullâ Sadrâ meyakini
konsep wujûd itu
univokal, dan wujûd
adalah dasar bagi realitas.
2 Umum-
khusus satu
sisi
Pengenalan Diri
sebagai
Langkah
Menuju
Pengetahuan
Sejati
Hamzah Fansûrî dan
Mullâ Sadrâ sama-sama
berpandangan bahwa
pengenalan diri sebagai
langkah menuju
pengetahuan sejati.
217
Namun Hamzah Fansûrî
lebih menekankan untuk
berproses melalui syariat
dan tarekat. Sementara
Mullâ Sadrâ lebih
menekankan untuk
berproses melalui
kesadaran rasional dalam
sistem filsafat.
3 Umum-
khusus
mutlak
Ilmu Hudhûrî
sebagai
Pengetahuan
Sejati
Hamzah Fansûrî dan
Mullâ Sadrâ sama-sama
mengakui perlunya ilmu
hudhûrî sebagai sumber
pengetahuan sejati.
Namun bagi Mullâ Sadrâ,
ilmu hudhûrî hanya
menjadi persiapan (awal)
bagi kegiatan berfilsafat.
Sementara bagi Hamzah
Fansûrî, ilmu hudhûrî
adalah kesempurnaan
dari pengetahuan.
4 Ekuivalen Eksistensi
Alam Potensial
Hamzah Fansûrî dan
Mullâ Sadrâ sama-sama
memahami bahwa alam
potensial itu sudah eksis
sejak sedia kala dan
menjadi sumber bagi
menjelmanya realitas
alam semesta.
5 Ekuivalen Kefakiran
Mutlak
Makhluk
kepada Khalik
Hamzah Fansûrî dan
Mullâ Sadrâ sama-sama
beritikad bahwa makhluk
itu benar-benar fakir
wujûd dan wujûd itu
hanya dari Khalik.
Sementara itu, pada sisi perbedaan, yang berada pada status nonekuivalen
dalam skema relasi, Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ memiliki sangat banyak
perbedaan yang tidak terhitung. Namun berdasarkan fokus penelitian, terdapat
beberapa berbedaan signifikan yang merupakan relasi nonekuivalen, yakni perbedaan
konteks kebudayaan, perbedaan pemahaman atas status kemajemukan realitas
218
eksternal, dan perbedaan multiperspektif varian dan sasaran kritikan. Konteks
kebudayaan yang berbeda dari Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ menentukan corak
yang berbeda dari kedua tokoh ini dalam menyampaikan ajarannya. Hamzah Fansûrî
perlu menyederhanakan Wujudiah dengan cara yang sederhana dan dalam bahasa
yang mudah dipahami masyarakat Melayu pada masanya. Sementara Mullâ Sadrâ
memiliki tuntutan untuk melanjutkan usaha sistesis berbagai model pemikiran dalam
karyanya.
Status kemajemukan alam dalam pandangan Hamzah Fansûrî tidak nyata
karena alam semesta dalam pandangannya hanyalah bayangan atau ‘athar dari Haqq
Ta’ala. Sementara Mullâ Sadrâ menegaskan bahwa kemajemukan itu riil berdasarkan
konsep taskîk al-wujûd. Meskipun demikian, konsep ambigu ini menimbulkan
perdebatan antar pemikir Sadrian. Sebagian meyakini taskîk al-wujûd adalah
pengantar bagi penjelasan wahdat al-wujûd. Sebagian lainnya meyakini taskîk al-
wujûd adalah final dari pemikiran Mullâ Sadrâ.
Perbedaan pandangan atas tiap-tiap tokoh menjadi bagian penting dari
perbedaan pemikiran Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ sebagai implikasi gagasan
masing-masing yang sangat ditentukan oleh konteks sosialnya yang berbeda. Ajaran
Hamzah Fansûrî meski sempat diterima pada masa Shams al-Dîn al-Sumatranî,
namun ditolak oleh Nûr al-Dîn al-Ranîrî. Cara pandang sebagaimana Nûr al-Dîn al-
Ranîrî terhadap pemikiran Wujudiah Hamzah Fansûrî secara umum berlaku hingga
hari ini.
Sementara gagasan Mullâ Sadrâ, meski sempat ditolak karena dicurigai
bertentangan dengan tradisi pemikiran dan mistisme Persia klasik, selanjutnya
diterima dengan baik dengan memunculkan multiperspektif. Pada satu sisi, pemikiran
Mullâ Sadrâ dipandang sebagai pemikiran mistisme, pada sisi lain dipandang sebagai
pemikiran filsafat.
Gambar 4. Perbedaan pemikiran Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ
No. Unit Perbedaan Keunikan Hamzah
Fansûrî Keunikan Mullâ Sadrâ
1 Perbedaan Konteks
Kebudayaan Hamzah Fansûrî
menyebarkan ajarannya
dalam bahasa yang
sederhana, puitis,
dengan analogi-analogi
yang mudah dipahami
masyarakat Melayu.
Budaya sisntesa berbagai
dimensi pemikiran Islam
di Persia menjadikan
Mullâ Sadrâ berdialog
dengan berbagai
khazanah pemikiran
Islam secara luas,
mendalam, dan panjang
lebar.
2 Perbedaan
Pemahaman atas
Status
Kemajemukan
Realitas Eksternal
Hamzah Fansûrî
menegaskaan tidak
menerima kemajemukan
realitas eksternal.
Mullâ Sadrâ menerima
kemajemukan (sekaligus
ketunggalan) realitas
eksternal (ambigu).
219
3 Multi Perspektif
Varian dan Sasaran
Kritikan
Ajaran Hamzah Fansûrî
awalnya diterima,
kemudian ditolak.
Ajaran Mullâ Sadrâ
awalnya ditolak,
kemudian diterima.
220
BAB VI
PENUTUP
Tradisi intelektual dan sosiokultural yang berbeda antara negeri Melayu dan
Persia pada sekitar abad ke-16 dan ke-17 berpengaruh pada lahirnya corak pemikiran
yang berbeda pada tiap-tiap konteks kebudayaan. Namun, kedua konteks itu sama-
sama telah melahirkan pemikir besar yang mampu melakukan kritik dan sintesis dari
khazanah pemikiran sebelumnya. Karena tradisi filsafat bercorak Aristotelian kurang
eksis di negeri Melayu, para pemikirnya kurang mendialogkan corak filsafat tersebut.
Sementara di negeri Persia, meskipun kecenderungan mistiknya juga sangat kuat
seperti di negeri Melayu, memiliki ruang yang luas dalam diskursus filsafat
Aristotelian. Hal ini tergambarkan dari corak pemikiran Persia, seperti Ibn Sînâ,
Syihab al-Dîn al-Suhrawardî, dan termasuk Mullâ Sadrâ yang terlibat dalam
diskursus filsafat Aristotelian. Sementara pemikir Melayu, seperti Hamzah Fansûrî
fokus pada diskursus tasawuf filosofis atau disebut juga dengan ‘irfan atau Wujudiah.
Perbedaan tradisi tersebut memengaruhi perbedaan jalan pemikiran Hamzah Fansûrî
dan Mullâ Sadrâ. Namun, keduanya memiliki kesamaan penting, yakni
mengembangkan gagasan pemikiran ketuhanan yang bercorak mistis sekaligus
filosofis. Dalam perspektif esensi pemikiran, keidentikan Hamzah Fansûrî dan Mullâ
Sadrâ adalah mereka sama-sama menerima wujûd sebagai konsep univokal dan
menjadi dasar bagi realitas.
Hamzah Fansûrî melanjutkan dan mengembangkan tradisi Wujudiah yang
telah lama berkembang dalam dunia Islam. Wujudiah yang dianggap sebagai kajian
berat dan rumit oleh Hamzah Fansûrî disampaikan dengan bahasa Melayu yang indah
dan menggunakan analogi-analogi yang mudah dipahami oleh masyarakatnya. Secara
umum, ajaran Hamzah Fansûrî menekankan agar manusia waspada atas
kecenderungan duniawi, pentingnya mengenal diri dan taat pada syariat, tarekat,
hakikat, dan makrifat agar memperoleh pengetahuan hakiki. Hamzah Fansûrî
menjelakan tujuh Sifat utama Haqq Ta’ala, yakni Hayy, 'Ilmû, Irâdat, Qudrat,
Kâlâm, Sâmî', dan Basyar. Hubungan antara ketunggalan dan kemajemukan
dijelaskan melalui sistem ta’ayyûn yang terdiri atas tujuh tingkatan, yakni ahadiyah,
wahdah, wahidiyah, ‘alam arwah, ta’ayyûn ‘alâm mitsal, ‘alâm ajsâm, dan ‘alam
insân. Dalam mengupayakan agar Wujudiah dapat dipahami dengan mudah,
khususnya dalam menjelaskan hubungan ketunggalan dan kemajemukan Hamzah
Fansûrî menggunakan analogi-analogi yang mudah dipahami masyarakat Melayu,
seperti tanah dan perabotan, kayu dan buah catur, cahaya dan sinarnya, laut dan
ombak, buah bundar, biji dan kandungan potensinya, cermin dan bayangannya,
manusia dan atributnya, sungai dan alirannya, air dan sifatnya, batu dan kepasifannya,
besi dan tukang besi, dan lainnya.
Sementara itu, Mullâ Sadrâ melanjutkan tradisi filsafat Islam tentang
pembahasan wujûd dengan melahirkan pandangan bahwa wujûd adalah dasar realitas
sementara mâhiyâh hanyalah konsepsi mental sebagai modus pengenaan wujûd.
Pandangan tersebut dikenal dengan istilah ashalat al-wujûd wa ‘itibar al-mâhiyâh.
Di samping itu, dalam filsafat Mullâ Sadrâ dikenal pula istilah taskîk al-wujûd.
221
Pandangan ini menegaskan bahwa wujûd yang tunggal itu sekaligus beragam. Mullâ
Sadrâ juga memperkenalkan konsep kausalitas yang unik. Dia menegaskan bahwa
akibat itu tidak memiliki entitas mandiri, kecuali hakikatnya adalah kebergantungan
itu sendiri atas sebab ('ain al-rabith bî al-illah). Diperkenalkan pula konsep basith al-
haqîqah, yaitu konsep yang menyatakan bahwa keseluruhan realitas itu diisi oleh satu
entitas tunggal yang sederhana, yakni wujûd. Mullâ Sadrâ juga melakukan suatu
revolusi dalam filsafat dengan menggagas konsep al-harakah al-jawhayiah. Dia
menyanggah para filosof sebelumnya dengan menegaskan bahwa pergerakan aksiden
merupakan indikasi bagi pergerakan substansi. Konsep ittihad aqil wa ma’qûl makin
menegaskan pandangan kesatuan wujûd yang menjelaskan bahwa pengetahuan
adalah terjadinya konfirmasi atas wujud yang tunggal.
Keunikan filsafat Mullâ Sadrâ dibandingkan berbagai aliran filsafat Islam
sebelumnya tampak sangat dipengaruhi oleh ajaran Wujudiah. Prinsip kemendasaran
wujud (ashalat al-wujûd) memang telah ada sejak filsafat Islam sebelumnya. Namun,
konsep-konsep, seperti kefakiran akibat dalam kausalitas (illiyah), hakikat sederhana
(basith al-haqîqah), gerak substansi (al-harakah al-jawhayiah), dan kesatuan subjek
dan objek (ittihad aqil wa ma’qûl) tidak lepas dari pengaruh ajaran Wujudiah.
Bahkan, konsep kemendasaran wujud (ashalat al-wujûd) sendiri yang dipertegas
kembali oleh Mullâ Sadrâ dalam filsafat Islam juga tidak terlepas dari pengaruh
Wujudiah. Karena itu, dapat dikatakan Mullâ Sadrâ mengambil semangat ontologis
dari ajaran Wujudiah dan membangun metodologi filsafatnya dengan mengambil
semangat rasional dari filsafat Islam, baik dari al-Hikmah al-Isyrâqiyyah maupun al-
Hikmah al-Masyâ'iyyah untuk membangun sebuah aliran baru dalam filsafat Islam
dengan dinamai al-Hikmah al-Muta’alliyah. Jadi, akomodasi Mullâ Sadrâ atas
Wujudiah yang kemungkinan besar diambil dari semangat Ibn ‘Arabî inilah yang
membuat ajaran Mullâ Sadrâ memiliki banyak kemiripan dengan ajaran Wujudiah
Hamzah Fansûrî yang tentunya juga sangat banyak menyerap ajaran Ibn ‘Arabî.
Hubungan ekuivalen itu, bahkan terletak pada landasan ontologisnya, yakni
kesamaan pandangan tentang univokasi dan kemendasaran wujud.
Dalam fokus penelitian, teridentifikasi lima persamaan dan tiga perbedaan.
Persamaannya, pertama adalah kesamaan iktikad bahwa istilah wujûd itu ekuivokal
dan menjadi dasar bagi realitas. Dalam ajaran Hamzah Fansûrî, wujûd yang
dianalogikan dengan tanah menjadi dasar bagi kemajemukan realitas, seperti kendi,
buyung, periuk, tempat, dan bejana. Dalam hal ini, Mullâ Sadrâ juga berpandangan
sama dengan menegaskan bahwa wujûd itu menjadi dasar realitas, sementara
mâhiyâh hanyalah konsepsi mental. Kedua, mereka juga memiliki kesamaan dalam
penegasan bahwa pengenalan diri sebagai awal menuju pengetahuan sejati. Maka dari
itu, ketiga, Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ sepakat bahwa pengetahuan sejati itu
adalah ilmu hudhûrî. Keempat, mereka juga sama-sama menerima eksistensi alam
potensial sebagai bekal bagi aktualitas alam semesta. Dalam hal ini, kelima, Hamzah
Fansûrî dan Mullâ Sadrâ juga sepakat bahwa makhluk itu fakir mutlak kepada Khalik.
Kefakirannya adalah kefakiran wujûd.
Dalam penelitian ini ditemukan tiga perbedaan penting antara pemikiran
Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ. Pertama adalah konteks sosial-budaya yang
222
berbeda yang melahirkan kultur ilmu pengetahuan yang berbeda. Hamzah Fansûrî
menyederhanakan ajaran Wujudiah dalam bentuk bahasa puitis dan analogi yang
mudah dipahami masyarakat Melayu. Sementara Mullâ Sadrâ melakukan sintesis
berbagai varian pemikiran yang luas karena sesuai dengan budaya ilmu pengetahuan
pada masanya, yakni para pemikirannya sedang berlomba melahirkan karya sintesis.
Kedua, perbedaannya adalah Hamzah Fansûrî mengakui dengan tegas bahwa realitas
eksternal itu hanyalah satu wujud. Sementara Mullâ Sadrâ sekalipun mengatakan
Mullâ Sadrâ itu tunggal, secara bersamaan Mullâ Sadrâ itu beragam. Ketiga,
perbedaannya adalah pada apresiasi masyarakatnya atas karya besar para intelektual
mereka. Karya Hamzah Fansûrî ditolak dan diklaim sesat setelahnya meskipun
sempat diapresiasi oleh Shams al-Dîn al-Sumatranî dan Sayf al-Rizâl. Sementara
karya Mullâ Sadrâ diterima dengan baik meskipun terjadi perdebatan penafsiran oleh
pengikutnya. Sebagian memaknai ajaran Mullâ Sadrâ dalam perspektif filsafat dan
sebagian memaknainya dalam perspektif tasawuf.
Masyarakat Indonesia perlu mempelajari semangat bangsa Persia dalam
mengapresiasi khazanah intelektual bangsanya sebagaimana dilakukan masyarakat
itu pada pemikiran Mullâ Sadrâ. Lagi pula, pemikiran Hamzah Fansûrî sebenarnya
memiliki kandungan nilai aksiologis yang kaya dan luas sehingga dapat ditawarkan
sebagai basis nilai dan semangat dalam berusaha mengatasi berbagai persoalan
kontemporer. Masyarakat Indonesia juga perlu mengambil semangat dari pemikiran
asing, seperti Mullâ Sadrâ, khususnya semangat sintesis berbagai khazanah ilmu
pengetahuan yang makin berkembang untuk membangun pemikiran yang
independen.
Masih sangat banyak tokoh yang dapat menjadi objek penelitian komparasi
pemikiran filsafat klasik. Kajian komparasi antara pemikir Nusantara sangat perlu
dilakukan untuk menemukan berbagai keunikan, persamaan, dan perbedaan tiap-tiap
tokoh. Setiap penelitian yang akan dilakukan perlu memperhatikan nilai
aksiologisnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat Indonesia.
Misalnya, penelitian tentang Ibn Sînâ, Syihab al-Dîn al-Suhrawardî, Abû Hamid al-
Ghazalî, dan lainnya dapat dilakukan kajian komparasi secara umum maupun
memotret aspek tertentu dari pemikiran mereka untuk dikomparasikan dengan
pemikir Nusantara, seperti Shams al-Dîn al-Sumatranî, Nûr al-Dîn al-Ranîrî, ‘Abd al-
Ra’uf al-Sinkilî, dan sebagainya.
Untuk kajian tentang pemikiran Wujudiah Hamzah Fansûrî, masih sangat
banyak bagiannya yang perlu dikaji secara mendalam. Berbagai pendekatan juga
dapat dilakukan untuk mengkaji pemikiran Hamzah Fansûrî. Penelitian tentang
Wujudiah Hamzah Fansûrî masih sangat minim dilakukan. Untuk itu, perlu penelitian
yang lebih banyak atas pemikiran Hamzah Fansûrî.
Naskah Asrâr masih membutuhkan kajian yang lebih serius dan mendalam
dari berbagai aspek dan menggunakan berbagai pendekatan. Naskah Syarâb juga
mengandung penjelasan metafisika ajaran Hamzah Fansûrî yang sangat mendalam.
Demikian juga naskah al-Muntâhî memerlukan kajian yang serius karena karya
tersebut telah membuat para penentang pemikiran Hamzah Fansûrî menjadi salah
paham. Untuk itu, diperlukan kajian yang sangat serius untuk mendalami naskah-
naskah tersebut. Tentu saja modal keilmuan yang cukup sangat diperlukan supaya
kajiannya menjadi jelas dan membantu menjadikan pemikiran Hamzah Fansûrî
223
menjadi lebih mudah dipahami, menyebar luas, dan bermanfaat bagi berbagai
kalangan.
Pemikiran-pemikiran Hamzah Fansûrî bila dikaji dengan cermat dapat
memberikan inspirasi dan pedoman mengatasi masalah-masalah masa kini dan masa
akan datang. Untuk itulah penelitian atas pemikiran Hamzah Fansûrî perlu terus
menerus dilakukan. Beberapa masalah yang mendesak untuk diatasi dewasa ini
adalah krisis intelektualitas dan spiritualitas, ekslusivitas dan intoletansi beragama,
kesetaraan gender, ekologi dan sains, ketimpangan sosial, dan lainnya. Melalui kajian
pemikiran Hamzah Fansûrî, permasalahan tersebut dapat ditawarkan solusinya.
Penelitian tentang Mullâ Sadrâ juga menyediakan sangat banyak aspek untuk
diteliti di masa selanjutnya. Dapat juga misalnya dilakukan kajian komparasi kembali
antara Hamzah Fansûrî dan Mullâ Sadrâ yang berfokus pada tema khusus seperti
epistemologi, etika, eskatologi, dan sebagainya. Tentu dua tema itu akan sangat
berguna bagi dunia ilmu pengetahuan dan sosial dalam rangka mengembangkan
konsep epistemologi ilmu pengetahuan, pembangunan konsep etika, dan eskatologi.
Sekalipun secara teologis gagasan Mullâ Sadrâ berbeda dengan masyarakat Indonesia
secara umum, tetapi sangat banyak aspek ilmu pengetahuan dan filsafatnya dapat
memberikan nilai aksiologis bagi masyarakat Indonesia.
224
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdullah, M. Amin. Antara Al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam. Bandung:
Mizan, 2002.
Açıkgenç, Alparslan. Being and Existence in Ṣadrā and Heidegger: A Comparative
Ontology. Kuala Lumpur: ISCAC, 1993.
Ahmad, Zakaria. Sekitar Keradjaan Atjeh dalam Tahun 1520-1675. Medan:
Monoro, 1972.
Akbarian, Reza. Trans-Subtantial Motion and Its Philosophical Consequencess,
dalam Mullâ Sadrâ and Transendent Philosophy; Islam-West Philosophical
Dialog. Shadra Islamic Philosophical Institute Publication. Teheran, 1999.
Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. A Commentary on the Hujjat Al-Shiddiq of Nûr
Al-Dîn Al-Ranirî. Kuala Lumpu: Kuala Lumpu, 1986.
———. Aims and Objectivesof Islamic Education. Jeddah: Jeddah: King Abdul
Aziz University, 1979.
———. Commens on The Re-Examination of Al-Ranirî ‘s Hujjat Al-Shiddiq:
Revitation. Kuala Lumpu: Muzium Negara, 1975.
———. Islam dan Sejarah Kebudayaan Melayu. Bandung: Mizan, 1990.
———. Raniri and the Wujûdiyah of 17th Century Acheh. Singapore: MBRAS,
1966.
———. The Mysticism of Hamzah Fansuri. Kuala Lumpur: University of Malaya
Press, 1970.
———. The Nature of Man and Phsycology of Human Soul. Kuala Lumpur:
ISTAC, 1990.
Al-Farabi. Ihsa‘ Al-‘Ulum. Diedit oleh Usman Amin. Kairo: Maktabah Angels Al-
Misriyyat, 1968.
———. Al-Fârâbî, Ara Ahl al-Madînah al Fâdhilah, (Mesir: Dâr wa Maktabah al-
Hilal, 1995).
Al-Ghazali, Abû Hamid, Mi’yâr Al-‘Ilm Fî Al-Manthiq. II. Beirut: Dâr al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 2013.
_________, Misykât al-Anwâr fî Tawhîd al-Jabbâr, Lebanon: Dâr al-Fikr, 1994.
_________, Tahâfut al-Falâsifah. Kairo: Dâr al-Ma’ârif, t.t..
Al-Kindi. On First Philosophy. Harvard: Harvard University Press, 1974.
Al-Mandary, Mustamin. Menuju Kesempurnaan: Pengantar Pemikiran Mulla
Sadra. Polman: Rumah Ilmu, 2018.
Al-Ranîrî, Nûr al-Dîn, Al-Tibyan fî Ma’rifat al-Adyân, Banda Aceh: PeNa, 2011.
_______. Rahasia Menyingkap Makrifat Allah. Jakarta: Diadat Media, 2009.
Al-Walid, Khalid. Perjalanan Jiwa Menuju Akhirat. Jakarta: Sadra Press, 2012.
———. Tasawuf Mulla Shadra: Konsep Ittihad Al-’Aqil Wa Al-Ma’qul dalam
Epistemologi Filsafat dan Makrifat Ilahiyyah. Bandung: MPress, 2005.
Amuli, Hasan Zadeh Al-Ta’lîqât ‘Alâ Al-Hikmah Al-Muta’aliyah fî al-Asfâr al-
'Aqliyyah al-Arba’ah Teheran: Mu‟assasah al-Ŝibâ‟ah wa al-Nasyr li Wizârah
al-Tsaqâfah wa al-Irsyâd al-Islâmî, 1386H.
———. Sarh Al-‘Uyûn fî Syarh Al-‘Uyûn. Qum: Markaz Intesyârât-e Daftar-e
Tablîghât-e Islâmî, 1421H.
225
Ansori, M. Afif. Tasawuf Falsafi Syaikh Hamzah Fansuri. Yogyakarta: Gelombang
Pasang, 2004.
'Arabî, Muhyiddin Ibn, Al-Fûtûhât Al-Makkiyah Vol. 2, Beirut: Dâr al-Shadir, t.t..
Azhari, Ichwan. Kapur Dari Barus: Islam dan Jaringan Perdagangan Kuno.
Medan, 2019.
Azra, Azyumardi. Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad
XVII & XVIII. Jakarta: Kencana, 2013.
Azwar, Pocut Haslinda Muda Dalam. Silsilah Raja-Raja Islam di Aceh:
Hubungannya dengan Raja-Raja Melayu Nusantara. Jakarta: Yayasan Tun Sri
Lanang, n.d.
Baehaqi, Imam. Kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Reinterpretasi.
Yogyakarta: LKiS, 2000.
Bagir, Haidar. Semesta Cinta. Bandung: Mizan, 2015.
Bakhsh, Wahid. Sufisme Islam. Jakarta: Sahara Publisher, 2004.
Bakhtiar, Amsal. Tasawuf dan Gerakan Tarekat. Bandung: Angkasa, 2003.
Baskara, Benny. Islam Bajo: Agama Orang Laut. Pamulang: Javanica, 2016.
Bertens, K. Panorama Filsafat Modern. Jakarta: Teraju, 2005.
Black, Deborah L. “Al-Farabi.” In History of Islamic Philosophy Vol. I, Diedit oleh
Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman, 224–225. London & New York:
Routledge, 1996.
———. “Knowledge ('ilm) and Certitude (Yaqīn) in Al-Fārābī’s Epistemology.”
Arabic Sciences and Philosophy, 2006.
Braginsky, Vladimir. Satukan Hangat dan Dingin: Kehidupan Hamzah Fansuri
Pemikir Dan Penyair Sufi Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka, 2003.
———. Yang Indah, Berfaedah Dan Kamal: Sejarah Sastra Melayu Dalam Abad
7-19. Jakarta: INIS, 1998.
Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. Kontribusi Charles Taylor, Syed Muhammad
Naquib Al-Attas, and Henry Corbin Dalam Studi Metafisika & Meta Teori
Terhadap Islam Nusantara Di Indonesia. Banda Aceh: BandarPublishing,
2017.
Chittick, Willam C. The Self-Disclosure of God: Principles of Ibn Al-’Arabi’s
Cosmology. New York: State University of New York Press, 1997.
Chittick, William C. Ibn ’Arabi: Heir to the Prophet. Oxford: Oneworld, 2005.
———. Imaginal Worlds: Ibn Al-’Arabi and the Problem of Religious Diversity.
New York: State University of New York Press, 1994.
———. The Sufi Doctrine of Rumi . Indiana: World Wisdom, Inc., 2005.
Chodjim, Achmad. Syeikh Siti Jenar: Makna Kematian. Jakarta: Baca, 2018.
———. Syekh Siti Jenar: Makrifat Dan Makna Kehidupan. Jakarta: Serambi, 2007.
Chodri, Abdul Ghaffar. The Mirror of Mohammed. Yogyakarta: Laksana, 2018.
Cibro, Ramli. Aksiologi Ma’rifat Hamzah Fansuri. Banda Aceh: Pade Books, 2017.
Corbin, Henry. Creative Imagination in the Sufism of Ibn Arabi. Princeton:
Princeton Legacy Library, 2014.
———. History of Islamic Philosophy. London & New York: Routledge, 2014.
Cruz, Melissa de la. Blue Bloods. Diterjemah. Jakarta: GagasMedia, 2011.
Dahlan, Abdul Aziz. Pemikiran Falsafi dalam Islam. Padang: IAIN IB Press, 2000.
226
———. Penilaian Teologis Atas Paham Wahdatul Wujûd dalam Tasawuf
Syamsuddin Sumatrani. Padang: IAIN Imam Bonjol Press, 1992.
Doorenbos, Johan. De Gefchriften van Hamzah Pansoeri. Leiden: Betteljee &
Terpstra, 1933.
Drewes, G.W.J., dan L.F Brakel. The Poems of Ḥamzah Fansûrî. Dordetch: Forish
Publication Holland, 1986.
El-Hanawy, Ahmed Fouad. “Al-Kindi.” Dalam A History of Muslim Philosophy
Vol. I, Diedit oleh M.M. Sharif, 421. III. New Delhi: Low Price Publications,
1995.
Epicurus. Seni Berbahagia. Yogyakarta: Basabasi, 2019.
Ernest, Carl W. Words of Ecstasy in Sufism. New York: State University of New
York Press, 1985.
Fadli, Abdul Hadi. Logika Praktis. Jakarta: Sadra Press, 2016.
Fakhry, Majid. A History of Islamic Philosophy. New York: Columbia University
Press, 1970.
Fansuri, Hamzah, “Asrâr Al-‘Arifîn,” dalam The Mysticism of Hamzah Fansuri, ed.
Syed Muhammad Naquib Al-Attas (Kuala Lumpur: University of Malaya
Press, 1970).
———. “Syarâb Al-Asyiqîn,” dalamThe Mysticism of Hamzah Fansuri, ed. Syed
Muhammad Naquib Al-Attas (Kuala Lumpur: University of Malaya Press,
1970),
———. “Al-Muntahî,”dalam The Mysticism of Hamzah Fansuri, ed. Syed
Muhammad Naquib Al-Attas (Kuala Lumpur: University of Malaya Press,
1970),
Fathurahman, Oman. Ithaf Al-Dhaki: Tafsir Wahdatul Wujûd Bagi Muslim
Nusantara. Bandung: Mizan, 2012.
———. Tanbih Al-Masyi: Menyoal Wahdatul Wujûd: Kasus Abdurrauf Singkel di
Aceh Abad 17. Bandung: Mizan, 1999.
Fazeli, Seyyed Ahmad. Mazhab Ibn Arabi: Mengurai Paradoksalitas Tasybih Dan
Tanzih. Translated. Jakarta: Sadra Press, 2016.
Fenton, Paul B. “Judaism and Sufism.” Dalam History of Islamic Philosophy Vol. I,
Diedit oleh Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman, 758. London & New
York: Routledge, 1995.
Gama, Cipta Bakti. Filsafat Jiwa: Dialektika Filsafat Islam dan Filsafat Barat
Kontemporer. Malang: Pustaka Sophia, 2018.
———. Fondasi Psikopatologi Islam. Malang: Pustaka Sophia, 2019.
Gharawiyan, Mohsen. Pengantar Memahami Buku Daras Filsafat Islam. Jakarta:
Sadra Press, 2012.
Guillot, C., dan Ludvik Kalus. Enskripsi Islam Tertua di Indonesia. Jakarta:
Gramedia, 2008.
Gullot, Claude. Barus: Seribu Tahun Yang Lalu. Jakarta: KPG, 2008.
———. Lobu Tua: Sejarah Awal Barus. Jakarta: Obor, 2002.
Hadi, Abdul W.M. Hamzah Fansuri: Risalah Tasawuf dan Puisi-Puisinya.
Bandung: Mizan, 1995.
———. Hermeneutika, Estetika, Dan Religiusitas: Esai-Esai Sastra Sufistik dan
Seni Rupa. Jakarta: Sadra Press, 2017.
227
———. Hermeneutika Sastra Barat dan Timur. Jakarta: Sadra Press, 2014.
———. Tasawuf Yang Tertindas: Kajian Hermeunetik Terhadap Karya Hamzah
Fansuri. Jakarta: Paramadina, 2001.
Hadi, Amirul. Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi. Jakarta: Obor, 2010.
———. “Islam and State in Sumatra: A Study of Seventeenth-Century Aceh a
Study of Seventeenth-Century Aceh (Islamic History and Civilization).”
Mc.Gill University, 1999.
Halverson, Jeffry R. Theology and Creed. dalam Sunni Islam: The Muslim
Brotherhood, Ash’Arism and Political Sunnism. New York: Palgrave
Macmillan, 2010.
Hamzuri, and Tiarma Rita Siregar. Permainan Tradisional Indonesia. Jakarta:
Direktorat Permuseuman, 1998.
Hanafi, Ahmad. Filsafat Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
Harahap, Syahrin. Islam Dan Modrrnitas: Dari Teori Modernisasi Hingga
Penegakan Kesalehan Modern. Jakarta: Kencana, 2015.
Hasjmy, Ali. Bunga Rampai Revolusi Dari Tanah Aceh. Jakarta: Bulan Bintang,
1978.
———. Nusantara, Syi’ah dan Ahlussunnah Saling Rebut Pengaruh dan
Kekuasaan Sejak Awal Sejarah Islam Di Kepulauan. Surabaya: Bina Ilmu,
1983.
———. Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia. Medan: Pustaka
Al-Ma’arif, 1981.
———. Ruba’i Hamzah Fansuri. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,
1976.
Heriyanto, Husein. Refleksi Kritis Terhadap Persepsi Populer Tentang Logika
Modern dan Indonsivisme. Jakarta, 2019.
Hitti, Philip K. History of the Arab. London: Macmillan, 1990.
Humaidi. Paradigma Sains Integratif Al-Farabi. Jakarta: Sadra Press, 2015.
Hurgronje, Snouck. Orang Aceh. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
Hye, M. Abdul. “Ash’arism.” In A History of Muslim Philosophy Vol. I, Diedit oleh
M.M. Syarif, 220. New Delhi: Adam Publisher & Distributors, 2001.
Inati, Shams. “Ibn Sînâ.” In History of Islamic Philosophy Vol. I, Diedit oleh
Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman, 231. London & New York:
Routledge, 1996.
Iqbal, Allama Sir Muhammad. Metafisika Persia: Suatu Sumbangan Untuk Sejarah
Filsafat Islam. Bandung: Mizan, 1990.
____. Rekonstruksi Pemikiran Religius dalam Islam, Bandung: Mizan, 2016.
Iqbal, Muhammad. Ibn Rusyd dan Averroisme: Pemberontakan Terhadap Agama.
Medan: Cipustakan Media Perintis, 2011.
Izutsu, Toshihiko. Struktur Metafisika Sabzawari. Bandung: Pustaka, 2003.
———. Sufism and Taoism: A Comparative Study of Key Philosophical Concepts.
Berkeley, Los Ageles London: University of California Press, 1983.
———. The Concept and Reality of Existence. Islamic Book Trus: Kuala Lumpu,
2007.
———. Struktur Metafisika Sabzawari, Bandung: Pustaka, 2003.
Jabir, Muhammad Nur. Wahdah Al-Wujûd Ibn ‘Arabî Dan Filsafat Wujûd Mulla
228
Sadrâ. Makassar: Chamran Press, 2012.
———. Perempuan: Perspektif Tasawuf. Makassar: Rumi Press, 2019.
Jackson, Roy. What Is Islamic Philosophy? London & New York: Routledge, 2014.
Kalin, Ibrahim. Knowledge in Later Islamic Philosophy. Knowledge in Later
Islamic Philosophy: Mulla Sadra on Existence, Intellect, and Intuition.
Oxford: Oxford University Press, 2010.
———. Mulla Sadra’s Transcendent Philosophy. Mulla Sadra’s Transcendent
Philosophy. Routledge, 2016.
Kamal, Zainun. Ibn Taimiyah Versus Para Filosof: Polemik Logika. Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2006.
Kartanegara, Mulyadhi. Gerbang Kearifan: Sebuah Pengantar Filsafat Islam.
Jakarta: Lentera Hati, 2006.
———. Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik. Bandung: Arasy, 2005.
———. Menembus Batas Waktu: Panorama Filsafat Islam, 2005.
———. Mengislamkan Nalar: Sebuah Respon Terhadap Modernitas. Jakarta:
Erlangga, 2007.
———. Menyelami Lubuk Tasawuf. Jakarta: Erlangga, 2006.
———. Menyibak Tirai Kejahilan: Pengantar Epistemologi Islam. Bandung:
Mizan, 2003.
Kennedy-Day, Kiki. “Al-Kindi.” Dalam Books of Definition in Islamic Philosophy,
19–31. Abingdon, UK: Taylor & Francis, 2010.
———. “Ibn Sînâ.” Dalam Books of Definition in Islamic Philosophy, 47–60.
Abingdon, UK: Taylor & Francis, 2010.
Kersten, Carool. A History of Islam in Indonesia. Edinburgh: Edinburgh University
Press, 2017.
———. Islam In Indonesia: The Contest for Society, Ideas and Values. New York:
Oxford University Press, 2015.
Kerwanto. Metode Tafsir Esoeklektik. Bandung: Mizan, 2018.
Khalidi, Muhammad Ali. Medieval Islamic Philosophical Writings. Diedit oleh
Muhammad Ali Khalidi. Medieval Islamic: Philosophical Writings.
Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
Kilic, Mahmud Erol. “Mysticism.” Dalam History of Islamic Philosophy Vol. II,
Diedit oleh Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman, 947. London & New
York: Routledge, 1996.
Kindî, Abû Isḥâq. On First Phylosophy. Harvard: Harvard University Press, 1974.
———. “Risâlah Fî Ḥudûd Al-Asyyâ.” Dalam Rasâ‛il Al-Kindiy Al-Falsafiyyah,
Diedit oleh Muḥammad ‘Abdulhâdî, 16. Kairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabiy, n.d.
Klein-Franke, Felix. “Al-Kindi.” dalam History of Islamic Philosophy Vol. I, Diedit
oleh Seyyed Hossein Nasr dan Oliver Leaman, 165. London & New York:
Routledge, 1996.
L. Askandar. Jiwa Bahari Sebagai Warisan Nenek Moyang Bangsa Indonesia.
Jakarta: Biro Sejarah Maritim AL, 1973.
Labib, Muhsin. Pemikiran Filsafat Ayatullah M.T. Misbah Yadzi. Jakarta: Sadra
Press, 2011.
Leaman, Oliver. A Brief Introduction to Islamic Philosophy. Cambridge: Policy
Press, 1999.
229
Lee, Jonathan Scott, dan Dominic J. O’Meara. “Plotinus: An Introduction to the
Enneads.” The Classical World (1996).
Lombard, Denys. Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636).
Jakarta: Gramedia, 2014.
Louis Massignon. “Mystical Theology.” Dalam The Passion of Al-Hallaj, Mystic
and Martyr of Islam, 3–52. Princeton University Press, 2019.
———. The Passion of Al-Hallaj: Mystic and Martyr of Islam. Princeton: Princeton
University Press, 1994.
———, Diwan Al-Hallaj. Yogyakarta: Putra Langit, 2003.
Madjid, Nurcholish, Ibn Taimiyah tentang Kalam dan Falsafah, Jakarta, Nurcholish
Madjid Society, 2020,
McGinnis, Jon. “Avicenna (Ibn Sînâ).” Dalam The History of Western Philosophy
of Religion, Diedit oleh Graham Oppy, 61–72. Durham: Acumen Publishing
Limited, 2011.
Melchert, Christopher. “Origins and Early Sufism.” Dalam The Cambridge
Companion to Sufism, 2014.
Miswari, Filsafat Terakhir, Lhokseumawe: Unimal Press, 20016.
_______. Filsafat Pertama, Lhokseumawe: Unimal Press, 20018.
Mitha, Farouk. Al-Ghazali and the Ismailis: Debate on Reason and Authority in
Medieval Islam. London & New York: I.B. Taurus Publisher, 2001.
Mohamad, Goenawan. Tuhan Dan Hal-Hal Yang Tak Selesai. Yogyakarta: Diva
Mujieb, M. Abdul, and H. Ahmad Ismail M Syafi’ah. Ensiklopedia Tasawuf Imam
Al-Ghazali. Jakarta: Hikmah, 2009.
Mulyati, Sri. Tasawuf Nusantara: Rangkaian Mutiara Sufi Terkemuka. Jakarta:
Kencana, 2017.
Muthahhari, Murtadha. Filsafat Hikmah: Pengantar Pemikiran Sadra. Bandung:
Mizan, 2002.
Nasr, Seyyed Hossein. Al-Hikmah Al-Muta’aliyah Mullâ Sadrâ : Sebuah Terobosan
Dalam Filsafat Islam, Jakarta: Sadra Press, 2017.
———. “Existence (Wujūd) and Quiddity (Māhiyyah) in Islamic Philosophy.”
International Philosophical Quarterly (1989).
———. “Introduction to Mystical Tradition.” In History of Islamic Philosophy Vol.
I, Diedit oleh Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman, 367. London & New
York: Routledge, 1996.
———. Islam and the Plight of Modern Man. Chicago: Kazi Publications, 2001.
———. Islamic Philosophy From Its Origin to the Present. New York: State
University of New York Press, 2006.
———. “Mir Damad.” In An Anthology of Philosophy in Persia, Vol. 5: From the
School of Shiraz to the Twentieth Century, Diedit oleh Seyyed Hossein Nasr
and Mehdi Aminrazavi, 200. London & New York: I.B. Taurus Publisher,
2015.
———. “The Meaning and Concept of Philosophy in Islam.” In History of Islamic
Philosophy Vol. I, Diedit oleh Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman, 21.
London & New York: Routledge, 1996.
———. Three Muslim Sages: Avicenna-Suhrawardi-Ibn Arabi. Harvard: Harvard
University Press, 1969.
230
Nasution, Hasan Bakti. “Hikmah Muta’alliyah: Analisa Terhadap Proses Sintesa
Filosofis Mulla Sadra.” IAIN Jakarta, 2001.
Nata, Abuddin. Studi Islam Komprehensif. Jakarta: Kencana, 2015.
Netton, Ian Richard. “Al-Farabi and His School.” Philosophy East and West (1994).
Noer, Kautsar Azhari, ed. “Al-Risalah Fi Al-’Ilm Al-Tshawwuf Al-Qusyairi.”
Dalam Warisan Agung Tasawuf: Mengenal Karya Besar Para Sufi, 240.
Jakarta: Sadra Press, 2015.
———. Ibn ‘Arabi: Wahdat Al-Wujûd dalam Perdebatan. Jakarta: Paramadina,
1995.
Nur, Syaifan. Filsafat Hikmah Mulla Sadra. Yogyakarta: Rausyan Fikr, 2012.
Nusution, Harun. Falsafat dan Mistisme dalam Islam: Filsafat Islam, Mistisme
Islam, dan Tasawuf. Jakarta: Bulan Bintang, 2018.
———. Teologi Islam. Jakarta: UIP, 2006.
Parsania, Hamid. Existence and the Fall: Spiritual Anthropology of Islam. London:
ICAS, 2006.
Perret, Daniel. Sejarah Johor-Riau-Lingga Sehingga 1914: Sebuah Esei Bibliografi.
Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Pelancongan
Malaysia, 1998.
Purwanto, Agus. Nalar Ayat-Ayat Semesta: Menjadikan Al-Quran Sebagai Basis
Konstruksi Ilmu Pengetahuan. Bandung: Mizan, 2015.
Qadir, C.A. Philosophy and Science in The Islamic World. London & New York:
Routledge, 2013.
Rahman, Fazlur. The Philosophy of Mulla Sadra (Sadr Al-Din Al-Shirazi). New York:
State University of New York Press ,1975.
Razavi, Mehdi Amin Suhrawardi and the School of Illumination, London: Routledge,
2014.
Russell, Bertrand. History of Western Philosophy. London & New York: Routledge,
2004.
Rusyd, Ibn, Tahâfut al- Tahâfut, Kairo: Dâr al-Ma’ârif, 1964.
Sadra, Mulla. Mulla Sadra, Al-Hikmah Muta’aliyyah fî Al-Asfâr Al-’Aqliyyah Al-
Arba’ah Vol. 1, Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-’Arabi, 2002.
———. Al-Hikmah Muta’aliyyah fî Al-Asfâr Al-’Aqliyyah Al-Arba’ah Vol. 2, Beirut:
Dar Ihya’ al-Turats al-’Arabi, 2002.
———. Al-Hikmah Muta’aliyyah fî Al-Asfâr Al-’Aqliyyah Al-Arba’ah Vol. 3, Beirut:
Dar Ihya’ al-Turats al-’Arabi, 2002.
———. Al-Hikmah Muta’aliyyah fî Al-Asfâr Al-’Aqliyyah Al-Arba’ah Vol. 8, Beirut:
Dar Ihya’ al-Turats al-’Arabi, 2002.
———. Al-Masya’ir, Teheran: The Institute for Culturan Studies, 1992.
———. Al-Syawâhid al-Rubûbiyyah fî al-Manâhij al-Sulûkiyyah. Teheran: Bustan
Kitab, 1388H.
Safi, Louay. The Foundation of Knowledge. Selangor: IIUM Press, 1996.
Said, Mohammad. Aceh Sepanjang Abad Vol. I. Medan: Waspada, n.d.
Sandigu. Wahdatul Wujûd: Polemik Pemikiran Sufistik Antara Hamzah Fansuri Dan
Syamsuddin Sumatrani DAN Nuruddin Al-Raniri. Yogyakarta: Gama Media,
2003.
Sheikh, M. Saeed. Islamic Philosophy. London: The Octagon Press, 1982.
231
Shihab, Quraish. Menyingkap Tabir Ilahi: Asmā Al-Husnā dalam Perspektif Al-
Qurʼan. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
______. (Penerj.) Alquran dan Maknanya. II. Jakarta: Lentera Hati, 2013.
Sholikhin, Muhammad. Menyatu Diri Dengan Ilahi. Yogyakarta: Narasi, 2010.
Siddiqui, Abdur Rashid. Qur’anic Keywords: A Reference Guide. Kano: The Islamic
Foundation, 2010.
Sînâ, Ibn, al-Nafs min Kitâb al-Syifâ, Qum: Markaz al-Nasyr-Maktab al-
I‟lâm al-Islâmî, 1417 H.
Siregar, Rivay. Dari Sufisme Klasik ke Neo-Sufisme. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
Siroj, KH. Said Aqid, Allah dan Semesta: Perspektif Tasawuf Falsafi, Jakarta:
Yayasan Said Aqid Siroj, 2021.
Smith, Margaret. Rābiʿa the Mystic and Her Fellow-Saints in Islām. Rabia the Mystic
and Her Fellow-Saints in Islam. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
Solihin, and Rosihon Anwar. Ilmu Tasawuf. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
Stace, Walter Terence. Mysticism and Philosophy. L.A.: Jeremy P. Tracher, 1980.
Suhrawardi, Sihabuddin. “Hikmah Al-Isyrâq.” In Majmû’ah Muśannafât Syaikh Al-
Isyrâq Vol. II, 11–13. Teheran: Pezhuhesgâh „Olûm-e Insânî va Moțâla‟ât-e
Farhangge, 1979.
Thabâthabâ’î, Muḥammad Ḥusein. Bidâyah Al-Ḥikmah. Qum: Muʽassasah an-Nasyr
al-Islâmî, 1428H.
———. Nihayah Al-Ḥikmah. Qum: Muʽassasah an-Nasyr al-Islâmî, 1428H.
Wijaya, Teuku Safir Iskandar. Falsafah Kalam. Lhokseumawe: Nadiya Foundation,
2003.
Yazdi, Mehdi Haeri. The Principles of Epistemology in Islamic Phlosophy:
Knowledge by Presence. New York: State University of New York Press, 1992.
Yazdī,Taqi Miṣbāḥ Muhammad. Al-Manhaj Al-Jadîd fî Ta’lîm Al-Falsafah Vol. 1.
Beirut: Dâr at-Ta’arûf li al-Mathbu’at, 1990.
Ziai, Hossein. “Shihab Al-Din Suhrawardi: Founder of the Illuminationist.” In
History of Islamic Philosophy Vol. I, Diedit oleh Seyyed Hossein Nasr and
Oliver Leaman, 434. London & New York: Routledge, 1996.
———. Suhrawardi Dan Filsafat Illuminasi. Jakarta: Sadra Press, 2012.
Zuchron, Daniel. Menggugat Manusia Dalam Konstitusi. Jakarta: Rayyana
Komunikasindo, 2017.
Jurnal:
Arif, Syamsuddin. “Filsafat Islam Antara Tradisi Dan Kontroversi.” TSAQAFAH 10,
no. 1 (May 31, 2014):
Arifin, Miftah. “Tuhfah Al-Mursalah: Studi Terhadap Pemikiran Martabat Tujuh Al-
Burhanpury.” AL-’Adalah 7, no. 2 (2004): 41–52.
Arrauf, Ismail Fahmi. “Mencerna Akar Filsafat Dalam Islam.” Ulumuna 17, no. 1
(November 8, 2017): 1–18.
http://ulumuna.or.id/index.php/ujis/article/view/236.
Bagir, Haidar. “Diskusi Pengalaman Religius.” Kanz Philosophia : A Journal for
Islamic Philosophy and Mysticism (2011).
232
Bawa, Dahlan Lama. “Pemikiran Pendidikan Mulla Shadra.” TARBAWI : Jurnal
Pendidikan Agama Islam 1, no. 2 (January 22, 2017): 123–128.
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/365.
Biran, Michal, and Thomas T. Allsen. “Culture and Conquest in Mongol Eurasia.”
Journal of the American Oriental Society (2003).
———. “Knowledge ('ilm) and Certitude (Yaqīn) in Al-Fārābī’s Epistemology.”
Arabic Sciences and Philosophy, 2006.
Braginsky, V.Y. “Some Remarks on the Structure of the ‘Sya’ir Perahu’by Hamzah
Fansuri.” Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the
Humanities and Social Sciences of Southeast Asia 131, no. 4 (January 1, 1975):
407–426. https://brill.com/abstract/journals/bki/131/4/article-p407_1.xml.
———. “Towards the Biography of Hamzah Fansuri. When Did Hamzah Live ? Data
From His Poems and Early European Accounts.” Archipel 57, no. 2 (1999):
135–175. https://www.persee.fr/doc/arch_0044-8613_1999_num_57_2_3521.
Brambor, Thomas, William Roberts Clark, and Matt Golder. “Understanding
Interaction Models: Improving Empirical Analyses.” Political Analysis 14, no.
1 (January 4, 2006): 63–82.
https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S1047198700001297/type/
journal_article.
Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. “A Study of Panglima La’ōt: An ‘Adat
Institution in Aceh.” Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies 55, no. 1 (June 26,
2017): 155–188. http://aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/55107.
__________. “Memahami Sejarah Intelektual Isaiah Berlin (1909-1997).” Esensia:
Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin (2016).
C. Inati, Shams, and Elsayed M. H. Omran. “Al-Junayd on Unification and Its Stages:
A Critical Examination.” Digest of Middle East Studies 3, no. 3 (July 1994):
23–35.
Chittick, Willam C. The Self-Disclosure of God: Principles of Ibn Al-’Arabi’s
Cosmology. New York: State University of New York Press, 1997.
Dabashi, Hamid. “’Ain Al-Qudhat Hamadani and Intellectual Climate in His Times.”
In History of Islamic Philosophy Vol. I, Diedit oleh Seyyed Hossein Nasr and
Oliver Leaman, 374. London & New York, 1996.
Dangauthier, Pierre, Ralf Herbrich, Tom Minka, and Thore Graepel. “TrueSkill
through Time: Revisiting the History of Chess.” In Advances in Neural
Information Processing Systems 20 - Proceedings of the 2007 Conference, 1–8.
NIPS Proceedings, 2009.
Downum, Garland, and Sufi Mutiur Rahman Bengalee. “The Life of Muhammad.”
Books Abroad 17, no. 1 (1943): 75.
https://www.jstor.org/stable/10.2307/40083214?origin=crossref.
van Ess, Josef, and Ali Hassan Abdel-Kader. “The Life, Personality and Writings of
Al-Junayd.” Oriens 20 (1967): 217.
Faiz, Faiz. “Eksistensialisme Mulla Sadra.” Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran
Islam (2015).
Fakhry, Majid. “Al-Farabi and the Reconciliation of Plato and Aristotle.” Journal of
the History of Ideas (1965).
Fazeli, Seyyed Ahmad. “Argumentasi Seputar Ineffability (Kualitas Tak
233
Tertuliskannya Pengalaman Mistis).” Kanz Philosophia : A Journal for Islamic
Philosophy and Mysticism 1, no. 1 (August 2011): 1.
———. “The System of Divine Manifestation in The Ibn ‘Arabian School of
Thought.” Kanz Philosophia : A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism
1, no. 2 (December 2011): 109.
Gama, Cipta Bakti. “Reduksionisme Eksplanatif Untuk Antropologi Transendental
Jawadi Amuli.” Kanz Philosophia : A Journal for Islamic Philosophy and
Mysticism 5, no. 2 (2015): 147–164.
Guillot, Claude, and Ludvik Kalus. “La Stèle Funéraire de Hamzah Fansuri.”
Archipel 60, no. 4 (2000): 3–24. https://www.persee.fr/doc/arch_0044-
8613_2000_num_60_4_3577.
Hadi, Amirul. “The Ṭāj Al-Salāṭīn and Acehnese History.” Al-Jami’ah: Journal of
Islamic Studies 42, no. 2 (2004): 258–293.
Hakiki, Kiki Muhamad. “Insan Kamil Dalam Perspektif Syaikh Abd Al-Karim Al-
Jili.” Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 3, no. 2 (December
30, 2018): 175–186.http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw/article/view/2287.
Hakimelahi, Abdolmajid, and Basrir Hamdani. “Belief in God by Intuitive
Knowledge.” Kanz Philosophia : A Journal for Islamic Philosophy and
Mysticism 6, no. 1 (June 13, 2016): 73.
Hambali, Yoyo. “Eksistensi Manusia Dalam Filsafat Pendidikan : Studi Komparatif
Filsafat Barat Dan Filsafat Islam.” Jurnal FAI: Turats 7, no. 1 (2011): 42–56.
Haq, Syed Nomanul. “Al-Farabi.” In The History of Western Philosophy of Religion,
Diedit oleh Graham Oppy, 47–60. Durham: Acumen Publishing Limited, 2011.
Herawati, Andi. “Concerning Ibn ’Arabi’s Account of Knowlegde of God (Ma’rifa)
Al Haqq.” Kanz Philosophia : A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism
3, no. 2 (December 25, 2013): 219.
http://journal.sadra.ac.id/index.php/kanzphilosophia/article/view/49.
Hidayatullah, Syarif. “Perspektif Filosofis Sir Muhammad Iqbal Tentang Pendidikan
Islam.” Jurnal Pendidikan Islam 2, no. 2 (January 1, 1970): 419.
http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/index.php/JPI/article/view/1154.
Holy, Ladislav, and V. Y. Mudimbe. “The Invention of Africa: Gnosis, Philosophy
and the Order of Knowledge.” Man 24, no. 2 (June 1989): 374.
https://www.jstor.org/stable/2803348?origin=crossref.
Hozien, Muhammad. “Philosophy, Theology and Mysticism in Medieval Islam.”
Journal of Islamic Philosophy 2, no. 1 (2006): 205–206.
http://www.pdcnet.org/oom/service?url_ver=Z39.88-
2004&rft_val_fmt=&rft.imuse_id=islamicphil_2006_0002_0001_0205_0206
&svc_id=info:www.pdcnet.org/collection.
Humaidi. “Mystical-Metaphysics: The Type of Islamic Philosophy in Nusantara in
the 17th-18th Century.” Jurnal Ushuluddin 27, no. 1 (July 30, 2019): 90.
http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/5438.
Hutahean, Juniar, and Cici Ramadayani Sirait. “Analisis Nilai Resistivitas Di Tanah
Peninggalan Sejarah Purbakala Menggunakan Metode Geolistrik Di Daerah
Lobu Tua Kabupaten Tapanuli Tengah.” Einstein e-Journal 5, no. 3 (January 9,
2019). https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/einsten/article/view/12003.
Imron, Muhammad Al, Sodikin Sodikin, and Romlah Romlah. “Meteor Dalam
234
Perspektif Al-Qur’an Dan Sains.” Indonesian Journal of Science and
Mathematics Education (2019).
Indrawan, Irjus. “Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam.” Al-Afkar : Jurnal
Keislaman & Peradaban 2, no. 1 (December 27, 2016).
http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/al-afkar/article/view/90.
Ivanow, W. “Some Poems in the Sabzawari Dialect.” Journal of the Royal Asiatic
Society of Great Britain & Ireland 59, no. 1 (January 15, 1927): 1–41.
https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0035869X00056914/type/
journal_article.
Jabir, Muhammad Nur. “Takwil Dalam Pandangan Mulla Sadra.” Kanz Philosophia :
A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism (2012).
Janssens, J. “Al-Ghazzali’s Tahafut: Is It Really a Rejection of Ibn Sînâ’s
Philosophy?” Journal of Islamic Studies 12, no. 1 (January 1, 2001): 1–17.
https://academic.oup.com/jis/article-lookup/doi/10.1093/jis/12.1.1.
Johns, A.H. “The Poems of Hamzah Fansuri.” Bijdragen tot de taal-, land- en
volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia
146, no. 2 (January 1, 1990): 325–331.
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/22134379-
90003221.
Kalin, Ibrahim. Knowledge in Later Islamic Philosophy. Knowledge in Later Islamic
Philosophy: Mulla Sadra on Existence, Intellect, and Intuition. Oxford: Oxford
University Press, 2010.
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199735242.
001.0001/acprof-9780199735242.
———. “Mulla Sadra and Metaaphysics: Modulation of Being.” Iranian Studies 43,
no. 4 (September 2010): 563–566.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00210862.2010.495583.
Kamal, Muhammad. “Existence and Non-Existence in Sabzawari’s Ontology.”
Sophia 51, no. 3 (September 14, 2012): 395–406.
http://link.springer.com/10.1007/s11841-011-0283-z.
———. Mulla Sadra’s Transcendent Philosophy. Mulla Sadra’s Transcendent
Philosophy. Routledge, 2016.
https://www.taylorfrancis.com/books/9781315596211.
Keeler, Annabel. “Wisdom in Controversy.” Journal of Sufi Studies 7, no. 1–2
(December 2018): 1–26.
Kerwanto. "Epistemologi Tafsir Mulla Sadra.” Jurnal Theologia 30, no. 1 (June 10,
2019): 23–50.
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/teologia/article/view/3238.
———. “Manusia Dan Kesempurnaannya (Telaah Psikologi Transendental Mullā
Shadrā).” Kanz Philosophia : A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism
5, no. 2 (December 20, 2015): 133.
http://journal.sadra.ac.id/index.php/kanzphilosophia/article/view/136.
———. “Pemikiran Filosofis Sadra Dalam Tafsir Al-Qur’an Al-Karim : Surah Al-
’A‘La.” Kanz Philosophia : A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism 4,
no. 2 (December 25, 2014): 23–50.
http://journal.sadra.ac.id/index.php/kanzphilosophia/article/view/63.
235
Khan, Israr Ahmad. “Identifying Entity and Attributes of God: An Islamic
Perspective Mengenal Pasti Entiti Dan Sifat-Sifat Allah: Satu Perspektif Islam.”
Journal of Islam in Asia (E-ISSN: 2289-8077) 13, no. 1 (July 19, 2016): 248–264.
https://journals.iium.edu.my/jiasia/index.php/Islam/article/view/531.
Miswari, “Mu‘ḍilat Al-Aqlīyah Al-Masīḥīyah Fī Ḥudūd Balad Al-Sharī‘ah Al-
Islāmīyah,” Studia Islamika (August 2018).
_______, “Cara Gila Jatuh Cinta: Analisa Qasidah Dan Muqataat Mansur Al-Hallaj,”
Al-Mabhats 4, no. 1 (2019): 51–74
_______, “Filosofi Komunikasi Spiritualitas: Huruf Sebagai Simbol Ontologi Dalam
Mistisme Ibn ’Arabî,” Al-Hikmah 9, no. 14 (2017): 12–30.
Koestoro, Lucas Partanda. “Gampong Pande, Situs Penting Di Ujung Utara Pulau
Sumatera.” Berkala Arkeologi SANGKHAKALA 19, no. 2 (May 21, 2017): 75.
http://sangkhakala.kemdikbud.go.id/index.php/SBA/article/view/27.
Koshul, Basit B. “Fazlur Rahman’s ‘Islam and Modernity’: Revisited.” Islamic Studie
33, no. 4 (1994): 403–417.
Laksana, Bagus. “The Mystery Of The Human Person : Mystical Anthropology In
Hamzah Fansuri’s Shair.” Kanz Philosophia : A Journal for Islamic Philosophy
and Mysticism 6, no. 1 (2016): 33–51.
Madjid, Nurcholish. “Pemikiran Filsafat Islam Di Dunia Modern: Problem
Perbenturan Antara Warisan Islam Dan Perkembangan Zaman.” Jurnal Al-
Hikmah 6 Juli-Okt (1992): 70.
Marpaung, Irwan Malik. “Alam Dalam Pandangan Abu Hamid Al-Ghazali.”
KALIMAH 12, no. 2 (September 15, 2014): 281.
http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah/article/view/240.
Mawardi. “Reaktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Kemajemukan
Sosial.” Substantia 17, no. April (2015): 55–66.
McGinnis, Jon. “Avicenna (Ibn Sînâ).” In The History of Western Philosophy of
Religion, Diedit oleh Graham Oppy, 61–72. Durham: Acumen Publishing
Limited, 2011.
———. “Scientific Methodologies in Medieval Islam.” Journal of the History of
Philosophy 41, no. 3 (2003): 307–327.
http://muse.jhu.edu/content/crossref/journals/journal_of_the_history_of_philos
ophy/v041/41.3mcginnis.html.
Mokhtar, Sarimah, Mohd Kashfi Mohd Jailani, Ab. Halim Tamuri, and Kamarulzama
Abdul Ghani. “Kajian Persepsi Penghayatan Akhlak Islam Dalam Kalangan
Pelajar Sekolah Menengah Di Selangor.” Global Journal Al-Thaqafah (2012).
Mondza, Iil Askar. “Rekaman Tsunami Di Gua Ek Leuti.” Tempo. Last modified
2019. Accessed February 6, 2020. https://majalah.tempo.co/read/ilmu-dan-
teknologi/158346/rekaman-tsunami-di-gua-ek-leuntie.
Mufid, Fathul. “Epistemologi Ilmu Hudhuri Mulla Shadra.” Al-Qalam 29, no. 2
(August 31, 2012): 215.
http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/866.
———. “Perkembangan Paradigma Epistemologi Dalam Filsafat Islam.” Ulumuna
(2013).
Mufrodi, H. Udi. “Alam Semesta Dan Keabsolutan Tuhan.” ALQALAM 22, no. 3
(December 30, 2005): 335.
236
http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/1365.
Muslih, Muhammad. “Kesadaran Intuitif Plus Cahaya Ilahiyah: Husserl Di Muka
Cermin Suhrawardi.” Tsaqafah 5, no. 1 (May 31, 2009): 29.
http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/146.
Nasution, Ismail Fahmi Arrauf. “Buku Panduan Pengkafiran: Evaluasi Kritis Tibyān
Fī Ma’rifat Al-Adyān Karya Nūr Al-Dīn Al-Ranīrī.” Jurnal Theologia 29, no.
1 (September 2, 2018): 59.
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/teologia/article/view/2313.
———. “Humanisasi Pendidikan Islam Melalui Antropologi Transendental Hamzah
Fansûrî.” Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam (2017).
———. “Termination OF Wahdatul Wujud In Islamic Civilization In Aceh: Critical
Analysis of Ithaf Ad-Dhaki, The Works of Ibrahim Kurani.” ADDIN 11, no. 2
(August 1, 2017): 401.
http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/view/3356.
———. “Waḥdat Al-Wujûd Dalam Alquran.” Mutawattir 6, no. 2 (2016): 258–283.
Nasution, Ismail Fahmi Arrauf, and Miswari. “Islam Agama Teror?: Analisis
Pembingkaian Berita Media Online Kompas.Com.” Al-Balagh 2, no. 1 (2017):
45–61.
_______. “Al-‘Ulamā’ Warathat Al-Anbiyā’: Modernity and Nurture of Authority in
Aceh Society,” Jurnal Theologia 30, no. 2 (December 23, 2019): 197,
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/teologia/article/view/3845.
Nio Song, Ai. “Evolusi Fotosintesis Pada Tumbuhan.” Jurnal Ilmiah Sains (2012).
Noer, Kautsar Azhari. “Tasawuf Dalam Peradaban Islam: Apresiasi Dan Kritik.”
Ulumuna (2017).
Nur, Syaifan. “Kritik Terhadap Pemikiran Tasawuf Al-Raniri.” Kanz Philosophia : A
Journal for Islamic Philosophy and Mysticism 3, no. 2 (2013): 137.
Rasmianto, Rasmianto. “Mengurai Problem Dikotomik Eksistensial Manusia Dalam
Perspektif Agama Dan Teori Evolusi.” El-Harakah 6, no. 2 (August 13, 2008):
75. http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/4669.
Rastam, Rohaimi, Yusri Mohamad Ramli, and Mohd Syukri Yeoh Abdullah.
“Penilaian Terhadap Pengajaran Syariat Islam Oleh Al-Hallaj, Hamzah Al-
Fansuri, Dan Shamsuddin Al-Sumatera’i.” International Journal of Islamic
Thought 12, no. 1 (December 1, 2017): 59–71. http://www.ukm.my/ijit/wp-
content/uploads/2017/11/IJIT-Vol-12-Dec-2017_6_59-71.pdf.
Reid, Anthony. “ Understanding Melayu (Malay) as a Source of Diverse Modern
Identities .” Journal of Southeast Asian Studies (2001).
Rescher, Nicholas. “Al-Farabi on Logical Tradition.” Journal of the History of Ideas
(1963).
Reza, Syah. “Konsep Nafs Menurut Ibnu Sina.” Kalimah 12, no. 2 (September 15,
2014): 263.
http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah/article/view/239.
Riahi, Ali Arshad. “A Study Of The Effect Of Human Soul On External Objects :
Between Copenhagen School And Mulla Sadra.” Kanz Philosophia : A Journal
for Islamic Philosophy and Mysticism (2015).
Riddell, Peter G. “Breaking the Hamzah Fansuri Barrier: Other Literary Windows
into Sumatran Islam in the Late Sixteenth Century CE.” Indonesia and the
237
Malay World 32, no. 93 (2004): 125–140.
Rusdiana, A. “Pemikiran Ahmad Tafsir Tentang Manajemen Pembentuk Insan
Kamil.” At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam (2017).
Rusli, Ris’an, and Y. Yanto. “Relevansi Dan Kontinuitas Pemikiran Islam Klasik
Dalam Intelektualisme Islam Melayu Nusantara.” Wawasan: Jurnal Ilmiah
Agama dan Sosial Budaya 3, no. 2 (December 30, 2018): 187–197.
http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw/article/view/4396.
Rustom, Mohammed. “Knowledge in Later Islamic Philosophy: Mullā Ṣadrā on
Existence, Intellect, and Intuition.” Iranian Studies 45, no. 3 (May 2012): 457–
461. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00210862.2012.655066.
Saleh, Sujiat Zubaidi. “Kritik Ibn Rusyd Terhadap Pandangan Para Filsuf Tentang
Ketuhanan.” Tsaqafah (2009).
Saliyo, Saliyo. “Selayang Pandang Harmonisasi Spiritual Sufi Dalam Psikologi
Agama.” Psikoislamika : Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam 11, no. 2
(December 30, 2014). http://ejournal.uin-
malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/6383.
Septiawadi, Septiawadi. “Pergolakan Pemikiran Tasawuf di Indonesia: Kajian Tokoh
Sufi Ar-Raniri.” Kalam 7, no. 1 (March 2, 2017): 183.
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/view/448.
Shah, Ainul Abidin. “Epistemologi Sufi : Perspektif Al-Hakim Al-Tirmidzi.” Kanz
Philosophia : A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism 2, no. 1 (June
23, 2012): 153.
http://journal.sadra.ac.id/index.php/kanzphilosophia/article/view/28.
Soleh, A. Khudori. “Mencermati Sejarah Perkembangan Filsafat Islam.” TSAQAFAH
10, no. 1 (May 31, 2014): 63.
http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/64.
Soleh, A Khudori. “Filsafat Isyraqi Suhrawardi.” Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu
Ushuluddin 12, no. 1 (January 22, 2011): 1. http://ejournal.uin-
suka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/view/121-01.
Stocker, Roman. “Marine Microbes See a Sea of Gradients.” Science, 2012.
Subahri, Subahri. “Aktualisasi Akhlak Dalam Pendidikan.” Islamuna: Jurnal Studi
Islam 2, no. 2 (December 5, 2015): 167.
http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/islamuna/article/view/660.
Suhrawardi, Sihabuddin. “Hikmah Al-Isyrâq.” In Majmû’ah Muśannafât Syaikh Al-
Isyrâq Vol. II, 11–13. Teheran: Pezhuhesgâh „Olûm-e Insânî va Moțâla‟ât-e
Farhangge, 1979.
Susilo, Benny. “Teori Gradasi : Komparasi Antara Ibn Sînâ, Suhrawardi Dan Mulla
Sadra.” Kanz Philosophia : A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism 5,
no. 2 (December 29, 2015): 159.
http://journal.sadra.ac.id/index.php/kanzphilosophia/article/view/139.
Tanusaputra, Daniel Nugraha. “Kerohanian Dan Pelayanan Seorang Hamba Tuhan.”
Veritas : Jurnal Teologi dan Pelayanan 14, no. 2 (October 1, 2013): 253–276.
https://ojs.seabs.ac.id/index.php/Veritas/article/view/281.
Ula, Miftahul. “Simbolisme Bahasa Sufi: Kajian Hermeneutika Terhadap Puisi
Hamzah Fansuri.” Religia 19, no. 2 (February 20, 2017): 26. http://e-
journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Religia/article/view/748.
238
Watt, W. Montgomery. “The Political Attitudes of the Mu’tazilah.” Journal of the
Royal Asiatic Society 95, no. 1–2 (April 15, 1963): 38–57.
https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0035869X00121392/type/
journal_article.
Yani, Zulkarnain. “Analisis Tematik Terhadap Syair Burung Pingai Karya Hamzah
Fansuri.” Penamas Balai Litbang Agama Jakarta XXII, no. Tema-Tema
Sufistik (2009): 20.
Zakaria, Zakaria. “Dakwah Sufistik Hamzah Fansuri: Kajian Substantif Terhadap
Syair Perahu.” Jurnal Ilmiah Islam Futura 13, no. 1 (2013): 105–125.
Zulkarnain, Dzikrullah. “Syaţaḥat Kaum Sufi: Sebuah Telaah Psikologis: Sebuah
Telaah Psikologis.” Smart 1, no. 1 (June 10, 2015): 77–110.
http://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/smart/article/view/232.
239
GLOSARI
‘Ayân tsabîtah adalah status eksistensi dalam irfan yang menjadi bekal, ketetapan,
dan potensi segala realitas sebelum teraktualisasi (menjelma).
‘Urafâ adalah pengajar dan penganut ajaran Irfan atau tasawuf falsafi.
Abstraksi adalah proses penggambaran atau pencerapan gagasan atas objek-objek
yang ditangkap indera, baik eksternal maupun internal, ke dalam dataran
konsep.
Akal merupakan salah satu alat ilmu dalam diri manusia yang berperan dalam
menangkap objek-objek abstrak seperti penalaran dan imajinasi,
Aksiologi ilmu merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang hakikat
manfaat suatu ilmu, antara lain mempertanyakan bagaimana dan untuk apa
manusia menggunakan ilmunya, kaitan penggunaannya dengan kaidah-
kaidah moral, cara menentukan objek kajian atau metodenya berdasarkan
pilihan moral ilmuwannya.
Al-insân al-kâmîl adalah istilah dalam irfan yang dialamatkan kepada seorang
manusia yang telah mencapai tingkatan spiritual tertinggi. Nabi Muhammad
adalah al-insân al-kâmîl.
Ashalât al-wujûd adalah prinsip ajaran Ibn Sînâ dan Mulla Sadrâ yang meyakini
bahwa wujûd itu menjadi dasar realitas sementara mâhiyah hanya tambahan
bagi wujûd.
Asrâr al-‘Ărifîn adalah karya Hamzah Fansûrî yang ditulis dalam bentuk prosa yang
berisi ajarannya tentang penjelasan filosofis tentang Wahdat al-Wujûd.
Basit al-haqîqah adalah konsep ajaran Mulla Sadra yang menjadi prinsip ajarannya
yang menjelaskan bahwa segala realitas itu prinsipnya adalah kesederhanaan
yakni wujûd yang tunggal tanpa komposisi.
Bayanî adalah pendekatan keilmuan yang menjadikan doktrin kitab suci sebagai
landasan pendekatannya. Pendekatan ini adalah andalan utama ilmu kalâm.
Burhanȋ adalah metode perolehan pengetahuan melalui sistematika penalaran
filosofis. Metode ini adalah landasan pendekatan filsafat
Demonstrasi merupakan bentuk inferensi atau pembentukan kesimpulan yang
merupakan konsekuensi logis dari premis-premis yang dibangun
sebelumnya.
Epistemologi merupakan cabang filsafat dan menjadi landasan bagi ilmu yang
membicarakan hakikat, sumber, struktur, metode, validitas, unsur, dasar, dan
segala hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan.
Fanâ merupakan keadaan atau modus hilangnya kesadaran inteleksi, imajinasi
sehingga yang tinggal hanya wujûd rohaninya kemudian mengalami
persatuan dengan yang transenden.
Filsafat adalah ilmu yang mempelajari segala yang ada dan mungkin ada secara
mendasar, rasional, kritis, dan radikal untuk menemukan hakikat persoalan
yang dikaji.
240
Hâitsiyah taqyîdîyah adalah model aspek kondisi yang menjadi konsep kunci untuk
menjelaskan hubungan ketunggalan dan kemajemukan.
Hakim adalah istilah untuk penganut dan pengajar hikmah.
Hati merupakan salah satu alat ilmu yang berperan dalam menangkap objek-objek
metafisika melalui kontak langsung dengan objek ilmunya.
Hayûlâ adalah istilah filosof Islam bagi salah satu kategori substansi yakni materi
primer salah satu kategori substansi lainnya yakni potensi aktualitas realitas
yang hanya menjelma apabila bergabung dengan sûrah (form).
Hikmah adalah bidang ilmu pengetahuan dalam pemikiran Islam yang membahas
tentang segala yang ada dan mungkin ada dan hal-hal yang berkaitan
dengannya dengan menjadikan burhanî sebagai landasan utama
pendekatannya. Ilmu ini disebut juga dengan filsafat Islam.
Hudhûrî merupakan bentuk pengetahuan langsung yang hadir dalam diri seseorang
(subjek) tanpa perantara dengan yang diketahui (objek).
Hûshûlî yakni pengetahuan yang hadir melalui proses konfirmasi dan afirmasi.
Ilmu adalah pengetahuan sistematis mengenai realitas ada yang dikonstruksi
berdasarkan metode yang relevan dengan objek yang menjadi wilayah
kajiannya.
Indra adalah salah satu alat ilmu yang dimiliki manusia yang berfungsi menangkap
objek-objek fisikal baik secara eksternal maupun internal.
Intuisi merupakan daya untuk memperoleh pengetahuan dengan segera dan langsung
tentang sesuatu, tanpa melalui prosedur logis yang baku.
Irfan adalah bidang ilmu tasawuf yang membahas persoalan-persoalan mistik secara
filosofis sehingga disebut juga dengan tasawuf falsafi yang dibedakan dengan
bidang tasawuf lain yakni tasawuf akhlak atau tasawuf amal.
Ittihad aqil wa ma’qûl yakni konsep dalam al-Hikmah al-Muta’alliyah yang
menjelaskan bahwa sebenarnya dalam pengetahuan itu, subjek dan objeknya
adalah satu kesatuan.
Kalâm yakni bidang ilmu pengetahuan dalam pemikiran Islam yang membahas
tentang Tuhan dan hal-hal yang berkaitan dengannya dengan menjadikan
bayanî sebagai landasan utama pendekatannya. Ilmu ini disebut juga dengan
teologi Islam.
Lâ ta’ayyûn adalah kondisi Haqq Ta’ala sebagai mâhiyah tidak terjangkau atau
disebut dengan ghaib al- ghûyûb.
Majâzî adalah istilah untuk wujûd yang hanya ada dalam ranah imajinasi tanpa
memiliki acuan pada realitas indrawi.
Maqâm adalah istilah untuk tingkatan capaian spiritual ‘urafâ.
241
mumkîn al-wujûd adalah materi primes yang wujûd nya masih sebatas potensialitas.
Ketika diberikan wujûd oleh wajîb al-wujûd bî nafsîhî maka menjadi Wajîb
al-wujûd bî ghayrihî.
Mutakallimîn adalah sebutan untuk penganut dan pengajar ilmu kalâm.
Ontologi adalah cabang filsafat yang berfokus mengjkaji segala yang ada dan
mungkin ada.
Realitas adalah eksistensi atau wujûd sesuatu pada ranah fisik, rasional, daan
metafisik.
Rûh idhâfî disebut juga haqîqat al-asyâ’ yaitu hakikat segala sesuatu yaitu sumber
segala jiwa yang berada pada ta’ayyûn awal dalam skema ontologi Hamzah
Fansûrî.
Ta’ayyûn adalah status tajallî Haqq Ta’ala ke dalam lima tingkatan.
Tajallî adalah manuifestasi Haqq Ta’ala yang digambarkan dalam skema ta’ayyûn.
Tajrȋbȋ adalah metode perolehan pengetauan melalui observasi dan eksperimen
indrawi yang berperan dalam menelaah objek-objek fisik. Metode ini adalah
landasan bagi pendekatan sains.
Tanzih adalah menyucikan Allah dari segala keidentikan apapun dengan makhluk.
Istilah ini disebut juga dengan transendensi.
taskîk al-wujûd adalah gradasi wujûd yang satu dalam berbagai status realitas dalam
al-Hikmah al-Muta’alliyah.
Tasybih adalah manifestasi Haqq Ta’ala dalam bentuk nama dan sifat. Istilah ini
disebut juga dengan manifestasi.
Wahdat al-wujûd adalah ajaran yang meyakini bahwa wujûd itu hanya satu. Ajaran
ini dipopulerkan oleh Ibn ‘Arabi dan para pengikutnya termasuk Hamzah
Fansûrî.
Wajîb al-wujûd adalah wujûd yang aktual dan niscaya.
Wajîb al-wujûd bî ghayrihî adalah wujûd aktual yang mengada karena diberikan
wujûd oleh wajîb al-wujûd bî nafsîhî.
wajîb al-wujûd bî nafsîhî adalah wujûd yang niscaya ada dengan dirinya sendiri yang
dinisbahkan kepada Haqq Ta’ala.
242
DAFTAR INDEKS
A
‘Abd al-Karim Al-Jîlî, 14
‘Abd al-Karîm al-Jîlî, 12, 30, 59
‘Abd al-Ra’uf al-Sinkilî, 26, 205, 217
‘Abd al-Rahman Jâmî, 45
‘Ain al-Qudat al-Hamadanî, 30, 45,
55, 56, 57
Abd al-Samad a-Falimbanî, 14
Abdul Aziz Dahlan, 62, 90
Abdul Hadi WM, 15, 18, 19, 20, 24,
27, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 81, 83,
86, 87, 90, 91, 93, 104, 123, 128,
131, 196
abstraksi, 40, 144, 148, 163, 167, 210
Abstraksi, 154, 234
Abû Hamid al-Ghazalî, 4, 20, 26, 42,
55, 58, 102, 178, 192, 194, 202,
217
Abû Mansûr al-Hallaj, 3, 10, 30, 45,
46, 48, 51, 54, 55, 57, 62, 64, 75,
79, 83, 207, 208
Abû Yazid al-Bistamî, 3, 30, 46, 47,
51, 53, 54, 56, 57, 64, 75, 79, 83,
190, 207, 208
Aceh Darussalam, 7, 10, 26, 66, 67,
92, 94, 95, 96, 97, 104, 193, 208
Achmad Chodjim, 6
Ahlû Sunnah wa al-Jama’ah, 3
akal, 35, 37, 38, 41, 44, 52, 59, 80,
84, 109, 143, 144, 145, 146, 148,
154, 167, 174, 175, 185, 187
Akal, 36, 41, 84, 143, 144, 148, 234
Aksiologi, 17, 220, 234
Alâ al-Daulah al-Simmananî, 48
A
Al-Fârâbî, 31, 36, 37, 38, 62, 84, 194,
219
Al-Furqan, 59
al-Futûhat al-Makkiyah, 84
al-harakah al-jawhayiah, 22, 28, 132,
149, 161, 170, 216
al-Hikmah al-Isyrâqiyyah, 2, 13, 63,
133, 168, 201, 208, 212, 216
al-Hikmah al-Masyâ'iyyah, 2, 4, 13,
34, 36, 38, 42, 133, 134, 156, 168,
201, 212, 216
al-Hikmah al-Muta’alliyah, 2, 5, 30,
64, 138, 158, 168, 216, 235, 236
Alî bin Abî Thalib, 75
al-insân al-kâmil, 59, 60, 78, 234
Al-Kindî, 31, 34, 35, 36, 194
Allama Sir Muhammad Iqbal, 4, 8,
20, 137, 190
al-Muta'alliyah fî al-Asfar 'Aqliyah
al-Arba'aah, 133
Al-Qur’an, 10, 25, 38, 47, 48, 49, 50,
51, 59, 68, 69, 74, 76, 82, 101, 102,
107, 109, 128, 129, 133, 143, 206,
229, 230
Anak Dagang, 86
Aristoteles, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 39,
42, 43, 62, 135, 138
Aristotelian, 4, 16, 32, 37, 38, 43,
142, 161, 168, 171, 200, 208, 209,
210, 211, 215
ashalat al-wujûd, 22, 28, 132, 138,
149, 152, 160, 169, 216
Ashalât al-wujûd, 234
Asrâr al-‘Ărifîn, 18, 86, 234
Ayan al-tsabîtah, 59, 60, 76
Ayân tsabîtah, 234
243
B
Bahâ al-Dîn al-‘Amilî, 133
Bahr al-‘Amiq, 106
Barus, 67, 93, 94, 95, 97, 99, 220,
221
barzakh, 60, 61, 85, 148
Basit al-haqîqah, 160, 234
basith al-haqîqah, 22, 28, 132, 149,
158, 159, 169, 216
bayanî, 109, 191, 193, 212, 235
Bayanî, 234
biji, 65, 73, 82, 103, 105, 106, 111,
112, 113, 114, 125, 126, 127, 174,
191, 195, 202, 206, 207, 208, 215
biji catur, 103, 105, 106, 174
Braginsky, 11, 19, 25, 67, 79, 88, 89,
94, 220, 227
Buah, 102, 111, 198
buah catur, 102, 103, 105, 106, 126,
198, 199
Burhanȋ, 234
C
catur, 65, 73, 96, 102, 103, 104, 105,
106, 124, 126, 174, 176, 184, 188,
198, 201, 204, 215
cermin, 59, 65, 73, 74, 76, 90, 111,
115, 116, 124, 126, 134, 151, 172,
173, 179, 200, 203, 208, 215
Cina, 92, 94, 95, 104
cinta, 47, 48, 89, 90, 113, 142, 161,
164, 170
D
Demonstrasi, 234
Dhu’nûn al-Misrî, 30, 51, 52, 54, 64
Drewes, 15, 18, 19, 20, 24, 62, 66,
67, 77, 80, 92, 93, 94, 104, 110,
121, 130, 221
E
emanasi, 31, 36, 37, 38, 60, 84, 102,
157, 174
Enneads, 35, 38, 224
Epistemologi, 48, 57, 70, 107, 135,
137, 139, 143, 158, 165, 187, 219,
223, 229, 231, 232, 234
Eropa, 67, 92, 95, 103, 104
F
Fadhl Allah al-Burhânpûrî, 14, 30, 56
Fanâ, 234
fânâ, 47, 53, 54, 55, 64, 73, 79, 80,
90, 122, 123, 129, 148, 190, 191,
193, 197
Fânâ, 79
Fansur, 65, 66, 67, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 119
Farîd al-Dîn Attâr, 88
Fazlur Rahman, 19, 20, 134, 136,
148, 155, 179, 180, 203, 230
filsafat Barat, 32, 39
G
gerak, 22, 28, 40, 41, 132, 134, 138,
142, 143, 148, 149, 161, 162, 163,
164, 170
H
Haidar Bagir, 6, 48, 61
Hâitsiyah, 209, 210, 235
hâitsiyah taqyîdîyah, 209, 210
Hâitsiyah taqyîdîyah, 209, 210, 235
Hakim, 48, 107, 232, 235
Hasan Bakti Nasution, 19, 20, 26,
133, 135, 136
Hasan Mu’allimî, 9, 209
Hasan Zâdeh Amûlî, 9, 196, 209
Hati, 31, 82, 109, 223, 226, 235
Hayûlâ, 235
244
Henry Corbin, 10, 17, 25, 62, 136,
220
hudhûrî, 11, 29, 33, 61, 73, 107, 109,
135, 143, 144, 146, 147, 148, 149,
151, 159, 160, 164, 165, 167, 168,
171, 173, 181, 183, 184, 185, 187,
189, 191, 193, 211, 212, 216
Hudhûrî, 183, 212, 235
hûlûl, 48, 56, 64
hushûlî, 109, 143, 144, 146, 147, 148,
149, 150, 167, 174, 181, 183, 184,
185, 187, 188, 190
Hûshûlî, 235
Hyle, 38
I
Ibn ‘Arabî, 3, 9, 15, 19, 22, 46, 48,
51, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 65, 78,
80, 81, 83, 84, 97, 108, 111, 113,
114, 116, 124, 127, 134, 142, 152,
153, 155, 157, 160, 161, 163, 164,
168, 174, 176, 177, 179, 187, 195,
197, 199, 202, 204, 206, 208, 209,
210, 216, 222
Ibn Farîd, 48
Ibn Rusyd, 4, 30, 155, 192, 194, 222,
232
Ibn Sînâ, 11, 13, 19, 30, 31, 32, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 57, 58, 62,
63, 77, 83, 84, 132, 134, 136, 138,
139, 142, 145, 150, 154, 163, 166,
168, 169, 180, 192, 194, 202, 215,
217, 222, 223, 224, 229, 230, 232,
234
Ibn Taimiyah, 42, 56, 223, 224
Ibrâhîm al-Kurânî, 3
Ibrahim Kalin, 17, 147
Ilahiyah, 13, 31, 32, 33, 35, 37, 44,
60, 61, 185, 213, 231
illiyah, 22, 28, 132, 149, 152, 160,
213
imkân al-faqr, 204
Indra, 77, 188, 235
Intuisi, 235
I
ittihad aqil wa ma’qûl, 22, 29, 132,
149, 152, 165, 186, 216
J
Jalal al-Dîn Rûmî, 79, 123, 125, 189
Jawadî Amulî, 133
jiwa, 33, 34, 35, 37, 41, 43, 46, 70,
86, 87, 88, 119, 128, 134, 135, 137,
142, 143, 144, 148, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 171, 174, 176, 180,
181, 185, 186, 188, 190, 192, 196,
203, 204, 205, 210, 236
Junayd al-Baghdadî, 10, 30, 54, 75,
79
K
Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad,
17, 25, 118
kanzân makfî, 113, 114, 118, 125,
129, 196
kanzân makhfiyyân, 113, 127
kasyaf, 34, 59, 78, 81, 135, 143, 147,
159
Kautsar Azhari Noer, 1, 48, 55, 56,
58, 62, 107
kosmopolitan, 95, 123, 124
Kudus, 93, 94
Kutaraja, 66, 93, 96
L
lâhût, 48, 64
laut, 58, 65, 72, 73, 74, 77, 80, 96,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
115, 120, 121, 125, 126, 128, 176,
181, 190, 191, 192, 198, 206, 208,
215
245
logika, 10, 12, 33, 35, 36, 37, 38, 42,
58, 133, 135, 143, 145, 191, 202,
213
M
Mahabaratha, 103
Maharaja Bakoy, 5, 12, 193, 202
mâhiyâh, 13, 31, 37, 38, 39, 40, 44,
77, 90, 134, 138, 139, 140, 141,
142, 147, 149, 150, 151, 152, 153,
155, 156, 160, 161, 168, 173, 175,
177, 178, 183, 184, 185, 188, 203,
209, 215, 216
Majapahit, 92, 193
Mantiqut Tayr’, 88
Martabat Tujuh, 10, 12, 66, 89, 226
matahari, 76, 96, 100, 101, 102, 124,
126, 178, 207
Melayu, 5, 9, 10, 16, 24, 25, 45, 46,
62, 65, 67, 73, 74, 76, 87, 89, 92,
93, 104, 106, 110, 111, 115, 117,
119, 121, 123, 124, 125, 171, 193,
199, 200, 202, 206, 208, 214, 215,
217, 219, 220, 231, 232
Minangkabau, 208
Mîr ‘Abd al-Qâshim Findirîskî, 133
Misykât al-Anwâr, 178, 219
Muhammad Hidâjî, 136
Muhammad Salîh Kassânî, 136
Muhammad Taqî Misbah Yazdî, 9,
30, 185, 210, 211
Mulla Alî Mudarris Zunûzî, 136
Mullâ Alî Nûrî, 136
Mullâ Hâdî Sabzawârî, 18, 19, 20, 30,
150, 209
Mulyadhi Kartanegara, 19, 26, 31,
40, 84, 137, 143
mumkîn al-wujûd, 156, 163, 180,
185, 236
Murtadha Mutahhari, 136, 161
mutakallimîn, 12, 31, 35, 47, 63, 75,
76, 78, 84, 97, 100, 109, 112, 113,
114, 117, 119, 120, 127, 133, 156,
178, 194, 202
N
Nasr al-Dîn Thûsî, 39, 133, 155
nâsut, 47, 64
Nazarî, 146
Neo-Platonis, 31, 32, 35, 37, 38
Nûr al-Dîn al-Ranîrî, 3, 4, 5, 8, 14,
15, 19, 26, 46, 62, 75, 200, 206,
207, 208, 214, 217
O
Ombak, 72, 106, 107, 108, 110
Ontologi, 11, 31, 58, 73, 138, 177,
230, 236
P
penalaran, 11, 31, 33, 36, 37, 40, 43,
44, 52, 75, 112, 135, 143, 234
perabotan, 65, 73, 86, 96, 97, 98, 99,
100, 102, 104, 124, 126, 176, 184,
185, 187, 198, 200, 201, 215
Persia, 4, 8, 16, 19, 20, 21, 26, 92, 93,
95, 101, 103, 104, 125, 132, 133,
134, 136, 146, 168, 171, 199, 200,
202, 205, 208, 214, 215, 217, 222,
224
Peureulak, 10, 92, 93
Plato, 33, 38, 84, 228
Plotinus, 35, 38, 84, 101, 224
Portugal, 96, 103, 193
Prima Causa, 30, 35, 38
proposisi, 31, 33, 43, 139, 144, 146,
147, 151, 157, 159, 164, 193, 199,
209, 211, 212
prosa, 5, 18, 24, 27, 46, 61, 67, 73,
74, 81, 125, 234
puisi, 21, 24, 46, 61, 67, 68, 70, 81,
83, 89, 123, 125, 133
246
Q
Qutb al-Dîn Shirazî, 30, 44
R
Rabi’ah al-Adawiyah, 30, 51, 52, 53,
64
Rûh idhâfî, 236
S
Sadr al-Dîn al-Qunâwî, 56
Samudra Pasai, 5, 10, 12, 67, 92, 97,
104, 105, 193, 200, 202
Sayf al-Rizâl, 206, 208, 217
Sayyid Hussîn Thabattâbâ'i, 9, 141,
144, 146, 150, 210, 211
Sayyid Nasîmî, 75
Sayyid Yadullah Yazdan Panah, 9,
209, 210
Seyyed Hossein Nasr, 1, 30, 32, 33,
34, 36, 39, 40, 45, 46, 48, 56, 101,
136, 138, 146, 147, 163, 178, 188,
209, 220, 221, 222, 223, 224, 226,
227
Shams al-Dîn al-Sumatranî, 18, 20,
25, 46, 49, 56, 62, 66, 78, 89, 90,
91, 199, 206, 214, 217
sintesis, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 26, 32, 125,
132, 154, 168, 200, 215, 217
Suryani, 34, 35
Syahri Nawi, 93
Syaikh ‘Abd al-Jalîl, 193
Syaikh Abdul Muhyî, 7
Syaikh Siti Jenar, 6, 7, 10, 12
Syaikh Yusuf al-Maqassarî, 7
Syair Burung Pinggai, 88
Syams al-Dîn al-Sumatranî, 10, 18
Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 9,
15, 17, 24, 25, 27, 45, 62, 65, 67,
73, 92, 99, 100, 185, 220, 221
Syihab al-Dîn al-Suhrawardî, 4, 8, 13,
19, 30, 31, 32, 33, 39, 42, 43, 44,
63, 84, 102, 132, 134, 135, 138,
139, 140, 142, 144, 145, 146, 147,
150, 155, 159, 163, 165, 168, 180,
186, 189, 193, 212, 215, 217
syu’un, 107
T
ta’ayyûn, 60, 74, 85, 124, 176, 186,
187, 191, 192, 198, 215, 235, 236
Tajallî, 58, 84, 236
Tajrȋbȋ, 236
tanah, 9, 65, 73, 74, 76, 77, 86, 93,
96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 122,
124, 125, 126, 171, 175, 176, 179,
183, 184, 186, 187, 198, 200, 201,
204, 211, 215, 216
tanzih, 57, 59, 64, 90
Tanzih, 60, 84, 90, 221, 236
Tapanuli, 94, 99, 229
tasawuf akhlak, 13, 46, 54, 212, 235
tasawuf falsafi, 6, 13, 51, 54, 235
tasawuf filosofis, 10, 11, 13, 22, 34,
48, 200, 209
taskîk al-wujûd, 135, 177, 187, 192,
204, 211, 214, 216, 236
tâskîk al-wujûd, 16, 22, 28, 132, 134,
149, 152, 153, 154, 155, 160, 169
tasybih, 57, 59, 64, 90
Tasybih, 60, 84, 221, 236
tasybîh, 59
Timur Tengah, 14, 92, 93, 94, 103,
104, 105, 110, 120, 122, 123, 124,
220
Toshihiko Izutsu, 19, 20, 21, 26, 28,
31, 130, 139
V
Vladimir Braginsky, 11, 18, 25, 67
W
Wahdah al-Syûhûd, 48
247
Wahdah al-Wujûd, 3, 12, 25, 48, 56,
57, 61, 78, 83, 85, 86, 104, 115,
156, 179, 186, 187, 198, 210
Wahdat al-wujûd, 236
Wajîb al-wujûd, 40, 236
Wajîb al-wujûd bî ghayrihî, 236
wajîb al-wujûd bî nafsîhî, 236
wâra', 48, 63
Y
Yunani, 32, 34, 35, 101, 120, 132,
141, 190, 194
Z
Zoroastrian, 8
248
BIODATA PENULIS
Miswari (Scopus id: 57203862000, Sinta id: 6012322) adalah pengajar filsafat Islam pada IAIN
Langsa, Aceh. Lahir di Paya Cut, Peusangan, Bireuen, Aceh, pada 12 September 1986. Menyelesaikan
magister filsafat Islam ICAS-Paramadina Jakarta pada 2014 dengan tesis berjudul “Hamzah Fansûrî dan
Pemikiran Wahdat Al-Wujûd dalam Asrar Al-‘Arifîn” di bawah bimbingan Prof. Dr. Abdul Hadi, WM.
Tesis tersebut telah diterbitkan oleh BasaBasi Yogyakarta pada 2018 dengan judul ‘Wahdah Al-Wujûd:
Konsep Kesatuan Wujûd Antara Hamba dan Tuhan Menurut Hamzah Fansuri’. Melanjutkan program
doktor filsafat Islam di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mengambil
Konsentrasi Filsafat Islam dengan disertasi berjudul “Kajian Perbandingan Wujudiah Hamzah Fansri dan
Filsafat Mulla Sadra”.
Pernah terlibat dalam organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) mulai dari Pengurus Daerah Bireuen,
Pengurus Wilayah Aceh sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pelajar pada 2006-2008, dan
Pengurus Besar bermarkas di Menteng Raya 58 Jakarta Pusat sebagai Ketua Bidang Eksternal pada 2010-
2012.
Telah menulis sekitar 40 artikel untuk berbagai jurnal terindeks Scopus, Sinta, dan lainnya. Di
antaranya adalah “Mu‘ḍilat al-aqlīyah alMasīḥīyah fī ḥudūd balad alsharī‘ah al-Islāmīyah” (Studia
Islamika, 2018), “Preserving Identity through Modernity: Dayah al-Aziziyah and Its Negotiations with
Modernity in Aceh” (Hayula, 2019), “al-‘Ulamā’ Warathat Al-Anbiyā’: Modernity and Nurture of
Authority in Aceh Society” (Theologia, 2019). Telah menulis sekitar 20 buku, diantaranya ‘Filsafat
Terakhir’ (Unimal Press, 2016 revisi Zahir Publishing, 2020), ‘Tasawuf Terakhir’ (Zahir Publishing, 2020),
dan ‘Teologi Terakhir’ (Zahir Publishing, 2021). Juga telah mengedit belasan buku yang telah diterbitkan
oleh Unimal Press dan Bandar Publishing.
Miswari dapat dihubungi WA 081295570747 dan email [email protected].