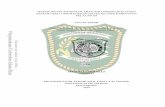Passive, 2-Stage Biofilter Treatment Systems for Reduction of ...
DISAIN IPAL PRAKTIS DENGAN BIOFILTER (ABIE WIWOHO, MSc
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of DISAIN IPAL PRAKTIS DENGAN BIOFILTER (ABIE WIWOHO, MSc
DISAIN IPAL PRAKTIS DENGAN BIOFILTER (ABIE WIWOHO, MSc)
5 June 2013 at 01:46
I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Rumah sakit, puskesmas, atau balai pengobatan adalah sarana
sosial yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk mencari kesembuhan
apabila sakit. Dimasa lalu lokasinya terletak di pinggiran kota
dan selalu dekat sungai, hal ini dimaksudkan agar tidak
menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitar, air limbahnya
hanya ditampung dalam penampungan sederhana kemudian efluennya
dibuang kedalam sungai.
Namun, dengan adanya perkembangan penduduk yang begitu cepat,
letak rumah sakit saat ini berada di tengah kawasan pemukiman
berdampingan dengan pusat usaha yang lain seperti warung makan,
super market, pasar, pabrik dll. Dengan semakin kompleknya jenis
pelayanan rumah sakit, maka jumlah dan jenis air limbahnya juga
semakin meningkat, maka jika pengelolaan air limbahnya tidak
baik sering menimbulkan konflik berkepanjangan dengan masyarakat
sekitar, mengancam kesehatan warga sekitar, mencemari sumber air,
menginfeksi permukaan tanah, badan air dengan bahan kimia atau
infeksius yang menimbulkan kerusakan berskala luas dan dalam
waktu yang lama.
Secara umum, kesadaran tentang keharusan membangun sarana
sanitasi agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan
sudah ada di masyarakat, hanya saja karena kurangnya informasi
yang cukup dan terbatasnya literature atau tenaga ahli menjadi
hambatan utama dalam membangun sarana sanitasi di rumah sakit
seperti , Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), tungku pembakar
sampah infeksius (incenerator), instalasi air bersih,
pengendalian serangga dan tikus dll.
Dalam buku ini dengan segala keterbatasan yang ada, penulis
memberikan panduan dan pengetahuan praktis tentang bagaimana
membuat IPAL rumah sakit secara mandiri, dikerjakan secara swa
kelola, diawasi oleh tenaga sanitasi setempat, menggunakan
material dan tenaga lokal yang ada. Buku ini dapat juga dijadikan
pedoman dalam upaya rehabilitasi IPAL rumah sakit yang belum
memuaskan baku mutu efluennya.
Dari pengalaman penulis sebagai konsultan IPAL di
rumah sakit dan tempat kost, atau sebagai penguji skripsi
mahasiswa dan diskusi intensif dengan para ahli di kampus serta
praktisi lapangan yang berhubungan dengan air limbah, maka
penulis mendapat kesimpulan tentang masalah pengelolaan air
limbah dirumah sakit, a.l :
1. Persepsi.
Mungkin karena terbatasnya tenaga ahli dan konsultan yang
menekuni desain IPAL maka dalam pembangunannya terjadi
penggelembungan harga, desainnya rumit sehingga biaya operasional
dan perawatannya mahal, suku cadang sulit dicari di pasar lokal
dll. Ada persepsi yang salah, yaitu bahwa membangun sarana IPAL
di rumah sakit atau pemukiman harus mahal, makin mahal makin
berkualitas efluennya. Padahal dengan membuat desain sendiri
terhadap Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hasilnya
juga dapat mencapai baku mutu seperti yang dipersyaratkan oleh
undang-undang. Harus disampaikan kepada para pembuat keputusan
proses pengolahan air limbah di rumah sakit itu mudah dipelajari,
dapat dikerjakan secara swa kelola dan dapat menggunakan bahan
lokal sehingga biayanya terjangakau.
2. Disain belum teruji
Karena panduan dalam proses pembuatan IPAL belum banyak
kepustakaannya, seringkali banyak menerima tawaran desain IPAL
yang tidak jelas rujukan atau teruji kinerjanya, ada baiknya
sebelum menerima desain yang dtawarkan oleh konsultan/kontraktor,
perlu dilakukan seminar tentang detail keunggulan dan kekurangan
dari konsep desain yang ditawarkan, dengan mmenghadirkan beberapa
ahli yang berpengalaman maka dari seminar tersebut dapat
diketahui banyak hal, terutama tentang dasar-dasar perhitungan
tentang proses, material, suku cadang, ketenagaan, dan lainnya.
Beberapa masalah yang sering timbul setelah
pembangunan/rehabilitasi IPAL antara lain:
a) Bak bocor, karena dalam pembangunan diawasi oleh petugas yang
tidak mengerti tentang bangunan yang berhubungan dengan
air, maka banyak tangki yang bocor, karena dasar dinding
IPAL tidak dipasang water stop , dinding atau dasar tangki
yang kualitas betonnya tidak standar atau tidak diberi
pelapis anti bocor. Bahkan ada IPAL yang terbuat dari serat
fiber yang tidak berkualitas sehingga setelah serah
terima, tangki nya banyak yang hancur dan rusak total.
b) Disain salah, adakalanya IPAL dibangun dengan perhitungan
kebutuhan sesaat saja tanpa memperhitungkan beban dimasa
mendatang, perhitungan waktu tinggal dan beban permukaan
yang terlalu kecil karena alasan lahan yang sempit atau
tidak cukup dana sehingga mengakibatkan tidak optimalnya
proses pengolahan dalam tangki pengolah air limbah, atau
mutu eflennnya sulit dicapai dan akhirnya memerlukan unit
pengolahan tambahan lagi untuk memperbaikinya. Kasus lain,
adalah desain tangki pegolahan pendahuluan (pre treatment)
dibuat dengan perhitungan waktu yang tidak cukup dan dibuat
asal asalan sehingga benda-benda padat masih dapat masuk
dalam proses pengolahan biologis, sehingga berbau dan banyak
kecoa atau tikus.
c) Tenaga, sebenarnya pemerintah, terutama Kementerian
Kesehatan mempunyai modal yang cukup dalam hal ketenagaan
yang mampu membuat desain / membangun /merehabilitasi IPAL
rumah sakit, puskesmas, tempat kos, pemukiman dll, yaitu
tenaga sanitasi (sanitarian). Dengan pelatihan beberapa sesi
saja maka tenaga sanitarian dengan kualifikasi pendidikan
setingkat D.III akan mampu membuat desain IPAL rumah sakit
secara baik dan benar, tanpa harus mendatangkan tenaga
ahli dari perguruan tinggi apalagi dari luar negeri.
d) Material lokal, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai
segala jenis material yang dibutuhkan dalam membuat sarana
IPAL dengan jumlah yang melimpah, dengan seleksi yang baik
dan penggunaan yang tepat maka kita dapat menekan biaya
seminimal mungkin sehingga harganya terjangkau. Sedangkan
peralatan yang masih harus dibeli adalah alat-alat
pabrikan seperti blower, diffuser, media bakteri dll namun
peralatan tersebut sekarang sudah tersedia di toko-toko di
kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya.
B. RESIKO, BAHAYA DAN DAMPAK.
Karena sifat pelayanan dan kegiatan yang dijalankan
oleh rumah sakit dan sarana kesehatan itu sangatlah komplek,
yang meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat,
pelayanan medik, penunjang medik dan non medik maka rumah sakit
juga merupakan depot segala macam penyakit yang adadi masyarakat.
Sasaran kritik sekarang adalah isu pengelolaan air limbah dirumah
sakit, dengan dampak luas yang merupakan interaksi berbagai
variabel yang komplek, sehingga mempunyai potensi resiko sbb:
a. Pencemaran lingkungan , yaitu adanya bahan bahan
pencemar infeksius yang dibuang kedalam lingkungan ,
jika tidak diolah dengan baik, dampaknya dapat luas dan
dalam waktu yang lama, dapat menimbulkan potensi
konflik dimasyarakat.
b. Infeksi silang, karena rumah sakit selalu dihuni,
dipergunakan dan dikunjungi oleh orang orang yang
rentan dan lemah terhadap penyakit, maka dapat
terjadi penularan penyakit secara langsung (cross
infection) melalui kontaminasi mati (environmental/ non
living infection) seperti air limbah dan sampah
medis, ataupun melalui serangga (vector borne
infection) sehingga dapat mengancam kesehatan
masyarakat sekitarnya.
c. Tuntutan hukum, saat ini masalah air limbah cair rumah
sakit mulai berkembang ke ranah hukum, yaitu dapat
dituntut dengan hukum perdata dan hukum pidana.
d. Green hospital, yaitu adanya tuntutan regulasi dan
mekanisme pasar global terkait dengan green building,
yaitu sebagai sistem rating yang terbagi atas 6 (enam)
aspek yang terdiri dari:
1 Tepat guna lahan (appropriate site
development/ASD)
2 Efisiensi energy & Refrigerant (energy efficiency
& refrigerant/EER)
3 Konversi air (water conservation/WAC)
4 Sumber dan siklus material (material resoursces &
cycle/MRC)
5 Pengelolaan limbah (waste& environment management)
Oleh karena itu air limbah rumah sakit harus menjadi isu
strategis bagi pengelola rumah sakit, keberadaan sarana IPAL
rumah sakit harus dirancang dan dikelola dengan system teknologi
dan managemen yang handal. IPAL harus dipahami sebagai sistem ,
bukan sebagai alat, sehingga harus dirancang oleh tenaga
professional dibidang pengelolaan air limbah.
C. TANGGUNG JAWAB PENGELOLA
Rumah sakit yang telah memiliki ijin dari pemerintah,
berwenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan susuai
peruntukannya, juga berwenang untuk mendapatkan keuntungan sesuai
yang diinginkan. Namun, Direksi yang berwenang mengelola Rumah
sakit juga harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap air limbah
yang dihasilkan dari aktifitas pelayanan yang terjadi dengan
sebaik baiknya agar tidak menimbulkan dampak
merugikan/membahayakan masyarakat maupun lingkungan sekitarnya
yaitu dengan prinsip pengelolaan sebagai berikut:
~ THE POLLUTER PAYS PRINCIPLE
Yaitu semua penghasil air limbah secara hukum dan
keuangan bertanggung jawab untuk menggunakan metode pengelolaan
yang aman dan ramah lingkungan. Dengan demikian , pimpinan rumah
sakit harus membuat anggaran yang cukup untuk mengelola sarana
IPAL, termasuk didalamnya penyediaan sumber daya manusianya.
~ THE PRECOUTIONARY PRINCIPLE
Yaitu prinsip kunci yang mengatur perlindungan
kesehatan & keselamatan melalui upaya penanganan secepat mungkin
dengan asumsi resiko yang dapat terjadi cukup signifikan.
Resiko adalah bersatunya komponen bahaya dengan paparan, resiko
dapat diabaikan kalau salah satu komponen dari bahaya atau
paparan tidak ada. Jadi, Resiko= bahaya x paparan.
~ THE DUTY OF CARE PRINCIPLE
Yaituprinsip kewaspadaan bagi petugas yang
menangani atau mengelola IPAL karenasecara etik bertanggung dalam
menerapkan tinggi.
~ PROXIMITY PRINSIPLE
Yaitu prinsip kedudukan dalam penanganan air
limbah berbahaya untuk meminimalkan resiko.
B. TUJUAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Yaitu mengurangi, memisahkan mengisolasi dan atau
menghancurkan sifat / kontaminan yang berbahaya dengan beberapa
upaya sbb:
~ mencegah dan menaggulangi pencemaran terhadap lingkungan, yaitu
mencegah padatan terapung, terendap, tersuspensi, dan bahan-bahan
organik lain yang merusak ekosistem perairan.
~ memulihkan kualitas lingkungsan hidup yang telah tercemar,
yaitu dengan membuat sistem IPAL yang baik, maka lingkungan yang
tercemar akan mudah dipulihkan kondisinya jika beban pencemaran
dapat ditekan sekecil mungkin, lingkungan ekosistem mempunyai
sistem pemulihan sendiri jika baku mutu efluen memenuhi syarat,
karena efluennya kaya dengan oksigen, maka secara kontinyu
membantu pemulihan ekosistem perairan yang sering disebut dengan
self purication.
~ meningkatkan kemampuan dan fungsi kualitas lingkungan, jika
rumah sakit secara mandiri mampu membangun sarana IPAL sehingga
mencapai baku mutu yang ditetapkan oleh undang undang, biasanya
akan menimbulkan esprit de corps diantara karyawannya, dengan percaya
diri mereka akan mudah diarahkan untuk meningkatkan kualitas
lingkungan sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan
sehat, bebas bau dan gangguan vector penyakit.
II. KIAT MEMILIH SISTEM IPAL UNTUK RUMAH SAKIT
Secara ideal didalam memilih IPAL untuk Rumah sakit atau
tempat pemukiman, hendaknya memperhatikan factor-factor sebagai
berikut :
Kualitas enfluen hasil olahan memenuhi standart dan stabil
Pengoperasiannya mudah, murah, sederahana namun efektif dan
efisien.
Kebutuhan lahan minimal dan konstruksi menggunakan bahan
baku setempat.
Disain proses ramah lingkungan, bebas dari bau, bising,
kotor serta gangguan tikus dan vektor.
Disain konstruksi dapatdikerjakan oleh tenaga setempat,
namun harus higienis dan tidak menggangguestetika.
Sudah teruji di banyak rumah sakit dan investasi
terjangkau.
Pelayanan saat operasional dan rekanan serta suku cadang
mudah
didapat.
Oleh karena itu sebelum menetapkan pilihan sistem IPAL
yangcocok untuk kondisi yang ada, maka perlu diadakan kajian dari
berbagai aspeksebagai bahan pertimbangan antara lain:
A. ASPEK LOKASI.
Rumah sakit yang berada di pemukiman, perlu pertimbangan
sentralisasi IPAL (desain terpadu).
Pertimbangan pengembangan kapasitas IPAL seiring
pengembangan kapasitas pelayanan atau penambahan jumlah
tempat tidur.
Multi fungsi lokasi fasilitas IPAL, misalnya dengan
pertamanan atau tempat parkir.
Lokasi IPAL berdekatan dengan air permukaan dan jauh dari
tempat pemukimann.
B. ASPEK SISTEM DAN TEKNOLOGI.
Kualitas dan karakter air limbah yang akan diolah.
Target hasil pengolahan yang diinginkan, seperti memenuhi
baku mutu yang ditetapkan atau untuk mendapatkan air daur
ulang (water recycling).
Karena IPAL adalah suatu sistem, dan bukan semata
alat/barang yang mudah diganti, maka perlu dipertimbangkan
beberapa hal sbb:
o Kesederhanaan disain (simpel), dan mudah
dikelola.
o Teknologi sederhana sehingga dapat dikelola oleh
tenga kerja setempat yang ada.
o Mengacu pada ketentuan danstandar yang ada,
seperti UU, PP, KepMen, SNI. Dll.
C. ASPEK MANAJEMEN. .
Penyediaan perangkat manajemen, (planning, organizing,
actuating dancontrolling).
Penyediaan perangkat penunjang, (man, money, material,
method, dan machine)
D. ASPEK SOSIAL BUDAYA
Perilaku pengunjung /masyarakat dalam membuang sampah
harus dapat perhatian utama, dalam membuang sampah,
adakalanya ditempat yang berhubungan dengan saluran
air limbah dipenuhi dengan sampah, seperti bungkus
makanan, bungkus obat-obatan, bekas pembalut, sisa makanan
dll yang dapat mengganggu kinerja IPAL.
Pemasangan perpipaan dan aksesoris juga memperhatikan aspek
sosial dan habitat vektor, dan tidak semata tergantung dari
perhitungan teknik.
Program pemeliaharaan yang seksama dan intensif.
E. ASPEK PEMBIAYAAN.
Biaya investasi, perlu kajian perbandingan harga
dengan IPAL lain yang sudah beroperasi, agar tidak terjadi
penggelembungan biaya pada saat investasi awal.
Kalkulasi biaya operasional dan pemeliharaan tiap bulan.
III.DASAR HUKUM
IV. PARAMETER DAN ISTILAH.
A. PARAMETER
Untuk mengetahui karakter air limbah dan membuat
perencanaan/monitoring terhadap IPAL di Rumah sakit, perlu
mempelajari parameter air limbah dengan dengan baik agardapat
mengetahui kandungan bahan bahan pencemar yang akan diolah.
Beberapaparameter penting minimal yang harus diketahui antara
lain :
1. BOD (Biochemical oxygen demand)
Pengetahuan terhadap parameter BOD didalam airlimbah sangat
berguna untuk menaksir beban pencemaran oleh bahan organic
danteknologi pengolahannya secara biologis. Angka BOD merupakan
petunjuk jumlahoksigen yang dibutuhkan oleh mikro organisme yang
menguraikan (mengoksidasi)hampir semua bahan organik terlarut dan
sebagian yang tersuspensi didalam airlimbah. Artinya nilai
BOD tidakmenunjukkan jumlah bahan organic yangada, tetapi hanya
mengukur secara relative jumlah oksigen yang dibutuhkan
mikroorganisme yang bersifat aerobic (secara alamiah) yang
membutuhkan oksigen gunakeperluan proses biokimia dalam
kehidupannya, yaitu untuk mengoksidasi bahanorganic, mensintesa
sel dan oksidasi sel, reaksi biokimianya sbb :
ü Oksidasi bahan organik
( C H2 O)n + nO2 enzim nCO2 + nH2O
+ panas
ü Sintesa sel
( C H2 O)n + NH3 + O2 enzim Komponen sel +
CO2 + H2O + panas
ü Oksidasi sel
Komponen sel + O2 enzim CO2 + H2O + NH3 panas
Didalam air limbah, bahan-bahan organik yang mengandung senyawa
nitrogen, sulfur, dan phospor dapat dioksidasi menjadi nitrat,
sulfat dan phospat. Di laboratorium, konsumsi oksigen dapat
diketahui dengan mengoksidasi air limbah pada suhu 20oC selama
5hari, dan nilai BOD diketaui dengan menghitung selisih konsumsi
oksigen terlarut sebelum dan sesudah inkubasi. Pengukuran selama
5 hari pada suhu 20oC hanya menghitung sebanyak 68% bahan organic
yang teroksidasi saja dan ini merupakan standar uji, karena untuk
mengoksidasi seluruh bahan organic secara sempurna diperlukan
waktu sekitar 20 hari sehingga tidak efisien.
Dalam membaca hasil uji BOD5 antara laboratorium
yang satu dengan lainnya dapat saja berbeda, atau hasil
analisanya seringkali tidak tepat, namun demikian analisa
sangatlah penting karena BOD mencerminkan proses alam yang hampir
sama dengan kenyataan, penyimpangan dapat terjadi karena adanya
proses mikrobiologis yang agak sulit diatur perilakunya.
2. COD (Chemical Oxygen Demand).
COD atau Chemical Oxygen Demand adalah kebutuhan
oksigen untuk menjalankan reaksi kimia atau jumlah oksigen yang
dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan bahan organic didalam air
limbah. Nilai COD merupakan salah satu parameter penting bagi
pencemaran air oleh bahan organic. Sejatinya, banyak bahan
organic yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme selama uji
BOD (yaitu BOD pada saat inkubasi 5 hari), atau bahkan sama
sekali tidak mengalami penguraian, namun bahan organic tersebut
harus diketahui jumlahnya karena berpengaruh terhadap kualitas
air limbah. Cara mengetahui jumlahnya yaitu dengan cara uji COD,
sehingga didalam pemeriksaan laboratorium nilai CODnya selalu
lebih besar dari nilai BOD untuk sampel yang sama.
Parameter COD memberikan gambaran nilai terhadap :
· Keberadaan bahan organic yang bersifat biodegradable
seperti yang dilakukan oleh bakteri pengurai selama uji BOD
selama 5 hari (BOD5)
· Keberadaan bahan organic yang bersifat biodegradable,
tetapi tidak dapat terurai selama uji BOD5 , tetapi dapat terurai
dalam pengolahan air limbah dengan proses biologis.
· Keberadaan bahan organic yangtidak mengalami penguraian
pada pengolahan secara biologis (non biodegradable).
· Adanya gangguan pada proses pengolahan air limbah,
karena adanya bahan organic yang bersifat toksik atau mengandung
bahan beracun.
Adapun senyawa lainyang merupakan bahan pencemar dan biasanya
menjadi sumber tingginya nilai COD adalah protein, minyak, lemak,
oli dan surfactant (detergen).
Dengan demikian, parameter COD merupakan gambaran dari kondisi
pencemaran dalam air yang dapat diartikan sbb:
� COD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi
semua bahan organic dalam air limbah tanpa membedakan yang
biodegradable dan yang non biodegradable.
3. Hubungan antara BOD denganCOD
Didalam menganalisa parameter hasil pemeriksaan laboratorium,
jika nilai BOD rendah dan nilai CODnya tinggi, maka perlu
mendapat perhatian khusus karena akan berpengaruh terhadap
kinerja IPAL di rumah sakit, yaitu adanya indikasi gangguan
terhadap pertumbuhan bakteri pengurai. Gangguan ini dapat
disebabkan oleh masuknya bahan-bahan beracun dalam air limbah
seperti Cr, Hg, Pb, CN, dll atau kekurangannutrien sehingga hasil
pemeriksaan parameter BODnya rendah, namun dilain pihaknilai COD
tinggi karena proses pemeriksaanya secara kimia yang tidak
dipengaruhioleh bakteri pengurai. Hubungan antaraBOD dengan COD
ini biasanya dinyatakan dalam bentuk nilai rasio perbandinganrata
rata, menurut Alaert dan Santika (1987) adalah seperti tabel
dibawah ini.
Tabel 1.
Rasio perbandingan rata rata antara BOD5dengan COD, pada bermacam
macam jenis air
0,4 - 0,6 Air limbah penduduk/domestic
0,6 Airlimbah penduduk/domestic setelah
mengalami pengendapan awal
0,2 Airlimbah penduduk/domestic setelah
diolah secara biologis
0,1 Airsungai yang tidak tercemar
0,5 - 0,65 Air limbah beracun dari industri organic
tanpa keracunan
0,0 - 0,2 Air limbah beracun dari
industryanorganik atau beracun
Selanjutnya nilai rasioini dapat digunakan sebagai rujukan dalam
membuat disain sistem IPAL yang menggunakan pengolahan biologis,
jika rasionya kurangdari 0,4 maka pengolahan secara biologis
tidak sesuai dan harus mencari sistempengolahan lain, namun jika
melebihi 0,6 sulit didapat karena nilai BOD selalulebih kecil
dari COD.
Oleh karena itu jika rumahsakit akan membuat disain pengolahan
secara biologis maka harus mengusahakankondisi air limbahnya
menyerupai air limbah domestic (air limbah penduduk)yaitu
mengusahakan rasio perbandingan parameter BOD dengan COD berkisar
antara 0,4– 0,6. Begitu juga untuk upaya monitoring kinerja IPAL
hendaknya selalumemperhatikan rasio antara BOD dengan COD ini
agar proses pengolahan air limbahdapat berjalan dengan optimal.
4. Hubungan antara BOD denganDO.
Hubungan parameter BODdengan DO (Disolved Oxygen / oksigen
terlarut) merupakan perbandingan terbalik,yaitu semakin tinggi
nilai BOD maka akan semakin rendah nilai DOnya
begitupulasebaliknya. Sebagai ilustrasi, jika didalam suatu
perairan belum tercemar ataumengandung sedikit bahan organic maka
bakteri aerobic akan menguraikan bahanbahan organic tanpa
menimbulkan perubahan dalam keseimbangan jumlah oksigendidalam
air. Artinya, oksigen yang digunakan bakteri untuk menguraikan
bahanbahan organic tersebut akan segera diganti secara alamiah
sehingga nilaioksigen terlarut (DO) relative sama jumlahnya.
Apabila ada bahanorganic masuk kedalam suatu perairan secara
berlebihan (timbul pencemaran),maka jumlah bakteri pengurai
aerobic akan tumbuh dengan pesat agar dapatmenguraikan bahan
organic yang berlebihanan tersebut, akibatnya kebutuhanoksigen
meningkat pula, dan akan mengambil oksigen terlarut yang ada
didalamair. Dengan demikian terjadi penurunan nilai oksigen
terlarut (DO) dansekaligus meningkatkan nilai BODnya, oleh karena
itu, agar kondisi oksigenterlarut didalam air tetap dalam
keseimbanganperlu ditambah dengan oksigen terlarut melalui
pasokan udara luar dari mesinblower.
5. TSS (Total Susoended solid)
Total suspended solid atau padatan tersuspensi total (TSS) adalah
residu dari padatan total yangtertahan oleh saringan dengan
ukuran partikel maksimal 2μm atau lebih besardari ukuran partikel
koloid. Yang termasuk TSS adalah lumpur, tanah liat, logamoksida,
sulfida, ganggang, bakteri dan jamur. TSS umumnya dihilangkan
denganflokulasi dan penyaringan. TSS memberikan kontribusi untuk
kekeruhan(turbidity) yang menghambat penetrasi cahayauntuk
fotosintesis dan visibilitas di perairan.
TSS (Total Suspended Solid) juga merupakan padatan
yangtersuspensi di dalam air berupa bahan-bahan organik dan
inorganic yang dapatdisaring dengan kertas millipore berporipori
0,45 μm.
Kekeruhanadalah kecenderungan ukuran sampel untuk menyebarkan
cahaya. Sementara hamburandiproduksi oleh adanya partikel
tersuspensi dalam sampel. Kekeruhan adalahmurni sebuah sifat
optik. Pola dan intensitas sebaran akan berbeda akibatperubahan
dengan ukuran dan bentuk partikel serta materi. Sebuah sampel
yangmengandung 1.000 mg / L dari fine talcum powder akan
memberikanpembacaan yang berbeda kekeruhan dari sampel yang
mengandung 1.000 mg / L coarselyground talc . Kedua sampel juga akan
memiliki pembacaan yang berbedakekeruhan dari sampel mengandung
1.000 mg / L ground pepper. Meskipun tiga sampel tersebut
mengandung nilai TSS yang sama.
6. Ammonia (NH3 ,NH4)
Amonia dihasilkan dari pembusukan proteinnabati, hewani dan
kotoran padat lain yang terbentuk pada saat penguraiansecara
anaerobic terhadapsenyawa urea danasam urine.
Amonia adalah senyawa kimia dengan rumus NH3. Biasanya senyawa
ini didapati berupagas dengan bau tajam yang khas (disebut bau
amonia). Walaupun amonia memiliki sumbangan pentingbagi
keberadaan nutrisi di bumi, amonia sendiri adalah senyawakaustik,
korosif, berbahaya dan dapat merusakkesehatan. Administrasi
Keselamatan danKesehatan Pekerjaan Amerika Serikat memberikan
batas 15 menit bagi kontak dengangas amonia
berkonsentrasi 35 ppm volum, atau 8 jam untuk 25 ppm volum.
Kontakdengan gas amonia berkonsentrasi tinggi dapat menyebabkan
kerusakan paru-parudan bahkan kematian.[5] Sekalipun amonia di AS
diatur sebagai gastak mudah terbakar, amonia masih digolongkan
sebagai bahan beracun jika terhirup, dan pengangkutan
amoniaberjumlah lebih besar dari 3.500 galon (13,248 L) harus
disertai surat izin.
Amonia yang digunakan secara komersialdinamakan amonia anhidrat.
Istilah ini menunjukkan tidak adanya air padabahan tersebut.
Karena amonia mendidih di suhu -33 °C, cairan amonia
harusdisimpan dalam tekanan tinggi atau temperatur amat rendah.
Walaupun begitu, kalor penguapannya amat tinggi sehingga dapat
ditangani dengantabungreaksi biasa didalam sungkup asap. "Amonia
rumah" atau amonium hidroksidaadalah larutan NH3 dalam
air.Konsentrasi larutan tersebut diukur dalam satuan baumé.
Produk larutan komersial amoniaberkonsentrasi tinggi biasanya
memiliki konsentrasi 26 derajat baumé (sekitar30 persen berat
amonia pada 15.5 °C).[7] Amonia yang berada di rumah
biasanyamemiliki konsentrasi 5 hingga 10 persen berat amonia.
Amonia umumnya bersifat basa (pKb=4.75), namun dapat juga
bertindaksebagai asam yang amat lemah (pKa=9.25).
7. MBAS. (methylene blueactive substances)
MBASadalah metode analisis Spektofotometri yaitu merupakan metode
pengukuran yangberdasarkan pada interaksi radiasi elektromagnetik
dengan partikel dan akibatdari interaksi tersebut menyebabkan
energi diserap atau dipancarkan olehpartikel dan dihubungkan pada
konsentrasi analik dalam larutan. Prinsip dasarspektofotometri
UV-Vis adalah ketika molekul mengabsorpsi radiasi UV ataufisibel
dengan panjang gelombang tertentu, elektron dalam molekul
akanmengalami transisi atau pengeksitasian dari tingkat energi
yang lebih rendah ketingkat energi yang lebih tinggi dan sifatnya
karakteristik pada setiapsenyawa. Penyerapan cahaya dari sumber
radiasi oleh molekul dapat terjadiapabila energi radiasi yang
dipancarkan atom analik tepat sama dengan perbedantingkat energi
transisi elektronnya (Rudi, 2004).
MethylineBlue bereaksi dengan surfaktan anion membentuk pasangan
ion baru yang terlarutdalam pelarut organik, intensitas warna
biru yang terbentuk diukur denganspektrofotometer dengan panjang
gelombang 652 nm. Serapan yang diukur setaradengan kadar
surfaktan anion (Anonim, 2009). Surfaktan merupakan zat
aktifpermukaan yang menyebabkan turunnya tegangan permukaan
cairan sehinggamemungkinkan bertindak sebagai zat pembersih atau
penghambur dalam industriatau rumah tangga. Untuk mengetahui
lebih jauh tentang zat pembersih yangmerupakan zat pembersih yang
berbentuk detergen sintetis maka berikut diuraikanuraian tentang
detergen.
DETERGEN
Setelahperang dunia ke II, dikembangkan bahanpencuci sintetis
yang dikenal dengan sebutan detergen sebagai alternatif
bahanpembersih konfensional seperti sabun, keunggulan detergen
ini adalah tidakmengendap bersama ion logam dalam air sadah. Dan
sekarang ini penggunaandetergen sangat meluas dimasyarakat
sebagai bahan pencuci atau pembersih yangsangat efektif dan
efesien.
Padaumumnya detergen mengandung bahan-bahan sebagai berikut :
a. Surfaktan (Surface active agent) yaitu zat aktifpermukaan
atau tensides adalah bahan utama dalam detergen yang
menyebabkanturunnya tegangan permukaan pada suatu cairan terutama
air. Surfaktanmenyebabkan pembentukan gelembung dan berpengaruh
terhadap permukaan lain yangmemungkinkan sebagai zat pembersih
dirumah tangga atau zat penghambur diindustri. Dengan sifat yang
dapat menurunkan tegangan permukaan tersebut makapartikel-
partikel (kotoran) yang menempel pada bahan yang di cuci
dapatterlepas dan melayang atau terlarut dalam air.
Surfaktandikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu :
o Sufaktan Anion
o Surfktan Kationik
o Surfaktan Non Ionik,dan
o Surfaktan Ampoteric (Zwi Tterionic)
Untuk bahan pencuci rumah tanggabiasanya digunakan jenis
surfaktan anionik (detergen). Dikenal dua macamdetergen anonik
yaitu ABS (Alkil Benzene Sulfonat) dan ALS (Alkil
LinearSulfonat). Pada awalnya detergen sintetis ini banyak
menggunakan senyawa p.Alkil Benzen Sulfonat (ABS) sebagai bahan
surfaktan yaitu gugus alkil yang banyakcabangnya. Bagian Alkil
senyawa ini disentesa dengan polimerisasi propilenadengan
melekatkan pada cincin senyawa Benzene. Namun, dalam praktek
penggunaansenyawa ABS ini tidak menguntungkan lingkungan karena
sifatnya yang sulitdiuraikan bakteri (non biodegredable). Senyawa
ABS ini sangat mengganggunproses dalam instalasi pengolahan air
limbah (IPAL) sehingga banyak sungai yangdicemari busa bahkan air
PAM pun mengandung busa, ABS juga toksik terhadapbiota air
seperti ikan, dll.
Pada saat ini industri mengubah detergenyang biodegredable yaitu
menggunakan senyawa Alkil Linear Sulfonat (ALS) denganstruktur
rantai lurus sebagai ganti rantai bercabang. Senyawa ini busanya
mudahdihilangkan dan toksisitasnya terhadap ikan sangat rendah.
b. Builder(Pembentuk)
Zatyang berfungsi meningkatkan efesiensi pencucian dari surfaktan
dengan caramenon aktifkan mineral penyebab kesadahan air. Bahan
builder antara lainPhosphates (Sodium Tri Poly Phosphat/STTP),
Asetat (Nitril Tri Acetate/NTA),EDTA (Ethylene Diamine Tertra
Acetat), dan Sitrat (asam sitrat).
c. Filler (Pengisi)
Bahan tambahandeterjen yang tidak mempunyai kemampuan
meningkatkan daya cuci, tetapi menambahkuantitas atau dapat
memadatkan dan memantapkan sehingga dapat menurunkanharga.
Contoh: Sodium sulfate.
d. Additivies(Zat Tambahan)
Bahansuplemen/tambahan untuk membuat produk lebih menarik,
misalnya pewangi,pelarut, pemutih, pewarna dan sebagainya yang
tidak berhubungan langsung dengandaya cuci
deterjen. Additivies ditambahkan untuk maksud komersialisasiproduk.
Contoh : Enzyme, Borax, Sodium chloride, CarboxyMethyl Cellulose (CMC)
dipakai agar kotoran yang telah dibawa oleh deterjenke dalam
larutan tidak kembali ke bahan cucian pada waktu mencuci.Wangi-
wangian atau parfum dipakai agar cucian berbau harum, sedangkan
airsebagai bahan pelarut (Admin, 2010).
TOKSISITASDETERGEN
Kemampuandeterjen untuk menghilangkan berbagai kotoran yang
menempel pada kain atauobjek lain, mengurangi keberadaan kuman
dan bakteri yang menyebabkan infeksi.Tanpa mengurangi makna
manfaat deterjen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,harus
diakui bahwa bahan kimia yang digunakan pada deterjen dapat
menimbulkandampak negatif baik terhadap kesehatan maupun
lingkungan. Dua bahan terpentingdari pembentuk deterjen yakni
surfaktan dan builders, diidentifikasimempunyai pengaruh langsung
dan tidak langsung terhadap manusia danlingkungannya (Admin,
2010).
Kadarsurfaktan 1 mg/liter dapat mengakibatkan terbentuknya busa
diperairan. Meskipuntidak bersifat toksik, keberadaan surfaktan
dapat menimbulkan rasa pada air dandapat menurunkan absorpsi
oksigen di perairan (Effendi, 2003).
Pengaruhlingkungan yang paling jelas adalah adanya busa pada
aliran sungai. Hynes danRoberts (1962), dalam studi aliran sungai
di Inggris yang menerima limbah airmengandung surfaktan (2-4 ppm)
tidak dapat mendeteksi perubahan apa pun dalamstruktur komunitas
biota air karena surfaktan (Connell, 1995).
Deterjen kerasberbahaya bagi ikan biarpun konsentrasinya kecil,
misalnya natrium dodesilbenzene sulfonat dapat merusak insang
ikan, biarpun hanya 5 ppm. Tanaman airjuga dapat menderita jika
kadar deterjen tinggi. Kemampuan fotosintetis dapatterhenti
(Sastrawijaya, 1991).
Permasalahanjuga ditimbulkan oleh deterjen yang mengandung banyak
polifosfat yang merupakanpenyusun deterjen yang masuk ke badan
air. Poliposfat dari deterjen inidiperkirakan memberikan
kontribusi sekitar 50 % dari seluruh fosfat yangterdapat
diperairan. Keberadaan fosfat yang berlebihan menstimulir
terjadinyaeutrofikasi(pengkayaan) perairan (Effendi, 2003).
PENENTUAN SURFAKTAN DENGANMETILEN BIRU
Metode inimembahas tentang perpindahan metilen biru yaitu larutan
kationik dari larutanair ke dalam larutan organik yang tidak
dapat campur dengan air sampai padatitik jenuh (keseimbangan).
Hal ini terjadi melalui formasi (ikatan) pasanganion antara anion
dari MBAS (methylene blue active substances) dan kationdari metilen
biru. Intensitas warna biru yang dihasilkan dalam fase
organikmerupakan ukuran dari MBAS (sebanding dengan jumlah
surfaktan). Surfaktan anionadalah salah satu dari zat yang paling
penting, alami dan sintetik yangmenunjukkan aktifitas dari
metilen biru. Metode MBAS berguna sebagai penentuankandungan
surfaktan anion dari air dan limbah, tetapi kemungkin adanya
bentuklain dari MBAS (selain interaksi antara metilen biru dan
surfaktan anion) harusselalu diperhatikan. Metode ini relatif
sangat sederhana dan pasti. Inti darimetode MBAS ini ada 3 secara
berurutan yaitu: Ekstraksi metilen biru dengansurfaktan anion
dari media larutan air ke dalam kloroform (CHCl3)kemudian diikuti
terpisahnya antara fase air dan organik dan pengukuran warnabiru
dalam CHCl3 dengan menggunakan alat spektrofotometri padapanjang
gelombang 652 nm (Franson, 1992). Batas deteksi surfaktan
anionmenggunakan pereaksi pengomplek metilen biru sebesar 0,026
mg/L, denganrata-rata persen perolehan kembali 92,3% (Rudi dkk.,
2004).
B. ISTILAH.
Istilah penting dalam pengolahan airlimbah yang perlu dipahami :
1. Debit
Jumlah Volume air dalam satuan waktu,yaitu produksi air limbah
dalam satu hari, biasanya satuannya adalah (m/hari),sedangkan air
minum satuannya adalah liter/detik. 1 hari = 24 jam = 1440 menit =
86400 detik.Debit air limbah diukur dengan penyekat Thomson / V-
notch dengan rumus Q = h⁵⁄₂ .
2. Waktu Tinggal
Waktu tinggal adalah lamanya air limbahberada di dalam suatu
tangki, yaitu dengan rumus Volume tangki / debit airlimbah
perhari dikalikan 24 jam/hari.
3. Beban Permukaan
Beban permukaan adalah debit air limbahperhari dibagi dengan luas
permukaan tangki. Beban permukaan ini menggambarkankecepatan air
limbah secara vertical yaitu aliran Up Flow atau Down Flow.
4. IRR
5. Sarang Tawon
Saran tawon adalah media plastic yangberbentuk seperti sarang
tawon, sebagai media pertumbuhan bakteri secaraanaerob/aerob.
Sarang tawon yang telah ditumbuhi oleh bakteri pengurai
tersebutsering disebut dengan biofilter.
C. Beban pencemaran
D.Dasar perhitungan kapasitas IPAL
Debitair limbah biasanya dihitung 80 % dari
kebutuhan air bersih, bagi mereka yangsulit menghitung volume air
limbah, maka dapat menggunakan rujukan SK GubernurDKI Jakarta No
122 Tahun 2004 (terlampir).
VI. PRINSIP DASAR TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR LIMBAH
Di dalam pengolahan air limbah,dikenal beberapa teknologi
tergantung dari karakter air limbahnya yangdipengaruhi oleh
kegiatan yang dijalankan, Secara garis besar teknologi
pengolahan airlimbah di rumah sakit dapat dikelompokkan sebagai
berikut:
· Teknik Pengolahan secaraFisika.
· Teknik Pengolahan secara kimiadan
· Teknik Pengolahan secara Biologi
Namun dalam prakteknya, penerapanketiga teknologi tersebut tidak
dapat berdiri sendiri melainkan merupakan gabungan dari ketiga
teknologitersebut, misalnya :
· Teknik Pengolahan secara fisika–kimia atau
· Teknik Pengolahan secaraFisika– Kimia-- Biologi
Mengingat banyaknya teknologi yangdapat dipilih sesuai kebutuhan
dan tujuan yang akan dicapai, maka penulis hanyamenyajikan
bahasan ringkas yang berhubungan dengan disain IPAL di rumah
sakit/pemukiman saja, agar pembahasan lebih ringkas.
A. PENGOLAHAN AIR LIMBAH SECARAFISIKA
Pengolahan secara fisikamenggunakan kaidah fisika untuk
memisahkan benda padat- kasar atau benda cair
pengganggu yang terbawa oleh aliran air limbah, seperti sampah,
pembalut, benda mengapung, bendamengendap, lemak, busa , daun,
sisa nasi, bekas perban dll. Beberapa teknologi yang dapat
digolongkan dalam pengolahansecara fisika antara lain:
1. Tapisan (Screen )
Yaitu memasang alat tapisan ditempat yang banyak dijumpai sampah
kasar agar tidak masuk dalam saluran pipa air limbah, seperti
dapur, ruang cuci,kamar mandi, bak kontrol dll. Bentuk lapisan
ini merupakan susunan beberapaderuji besi tahan karat dan
ukurannya bermacam macam tergantung dari letak dankarakter benda-
kasar yang akan ditapis. Ukuran antar deruji biasanya antara 5
mm sampai 15 mm, dan benda bendahasil tapisan dibuang secara
berkal dengan cara di bakar di dalam tungkupembakar (incenerator)
2. Pengendapan (sedimentasi).
Benda benda yang mempunya rapatmasa lebih besar dari air limbah,
seperti pasir, abu gosok, sludge dapat disisihkan dengan
carapengendapan. Tangki pengendapan biasanya didisain dengan cara
memperlambatkecepatan aliran seoptimal mungkin untukmengendapkan
benda benda yang mempunyairapat masa besar.
Pengaturan kecepatan aliran ini menggunakanrumus Q = V A, dengan
memperlebar luaspermukaan pada tangki yang dilewati yang
dilewati oleh air limbah maka akanterjadi pengendapan
Untuk tangki yang alirannyavertikal kecepatan aliran diatur
dengan kecepatansangat rendah agar terjadi proses pengendapan,
pengaturan kecepatan ini dikenaldengan istilah beban permukaan,
dengan rumus Q/A, standart yang dikehendaki antara 20 – 50
m3/m2/hari. (JWWA).
3. Pengapungan ( floatasi).
Untuk benda benda yang rapatmasanya lebih kecil dari air
limbah dapat disishkan dengan pengapungan (floatasi), yaitu
dengan mengatur kecepatan dan arah aliran keluar (efluen)nya
diaturmelewati bagian bawah bangunan, dan dalam keadaan tertentu
ditambahkan sistemdispersi udara dari bagian bawah agar partikel
lebih cepat mengapungdipermukaan air. Untuk bahan cair asal
dapur, seperti lemak, minyak busa dllproses pengapungan terjadi
pada tangki penangkap lemak dibagian atas,lapisan bagian atas
ini lama kelamaanakan mengering berbentuk benda mengapung yang
disebut dengan scum. Scum yangsudah tebal dan menutupi permukaan
tangki harus dibuang secara berkala, dengancara dibakar dalam
incenerator (tungku pembakar sampah).
4. Dewatering (pengurangan kadarair)
Hasil samping dari prosespengolahan air limbah adalah lumpur
(sludge), lumpur ini setelah mengendapdalam jangka waktu lama
didalam tangki akan berubah bentuk menjadi bahan stabil dan
volumenya susut antara 80 – 90 % dari semula, namunkarena lumpur
ini berasal dari rumahsakit masih, dianggap berbahaya karena
bersifat infectious, dan harus dibuangsesuai standar yang
berlaku.
Cara pengeringan (dewatering)sederhana antara lain :
ü Pengeringan dengan sinar matahari, yaitu mengalirkan lumpur
pada unggun pasir, makaair akan mengalir kebagian bawah danlama
kelamaan akan mengering oleh panas sinar matahari
~ Pemerasan dengan mesin kempa,lumpur dimasukkan kedalam
kantungberpori, lalu diperas dengantekanan besar atau diberi
putaran sentrifugal maka akan terpisah dengan air, lumpurkering
perlu didisfeksi sebelum dibuangkedalam lingkungan.
B. PENGOLAHAN AIR LIMBAH SECARA KIMIA.
Untuk mengolah airlimbah dirumah sakit/ pemukiman juga
menggunakan bahan bahan kimia tertentu untuk memperbaiki
kualitas efluennya, Didalam praktek, teknik kimia yangdigunakan
didalam pengolahan air limbahantara lain :
~ Teknik oksidasi, teknikoksidasi atau yang dikenal dengan istilah
Advanced Oxidation Processes (AOPs)mendapat perhatian karena
kemampuannya menguraikan bahan bahan organic yangsulit/tidak
dapat diuraikan dengan proses pengolahan biologi atau
saringanmembrane. Teknik oksidasi ini juga diterapkan dalam
proses pengolahan airminum. Teknik oksidasi merupakan campuran
beberapa proses yang menggunakanoksidator kuat, seperti ozon atau
hydrogrn peroxide dengan ultraviolet light,titanium oxide, photo
catalyst, sonolysis, electron beam, electrical dischargesdll yang
dapat menghasilkan hydroxylradical (OH). OH merupakan senyawa aktif
yang memiliki potensi oksidasitinggi sebesar 2.8 v melebihi ozon
yang hanya memiliki 2.07 v saja, sehingga OHsangat reaktif
terhadap bahan pencemar disekitarnya tanpa terkecuali, bahkan
OHdapat bereaksi dengan OH juga membentuk hydrogen peroxide
(H2O2).
AOPs dar kombinasi ozon, hydrogen peroxide, dan ultraviolet
lightmerupakan teknik oksidasi yang paling banyak digunakan,
kemudian diikuti olehmetoda titanium oxide dan fenton reaction,
sonolysis,electron beam yang masihdalam tahap penelitian. Untuk
air limbah medis penggunaan metoda AOPs denganO3/H2O2, O3/UV dan
UV/H2O2 sangat efektif menguraikan bahan pencemar sisa obatyang
mengandung senya atrazineyangtidak dapat diuraikian dengan proses
biologis.
~ Teknik disinfeksi, yaitu penggunaan bahan kimia sebagai disinfektan
untukmenghilangkan bakteri pathogen agar tidak membahayakan
masyarakat sekitar, beberapabahan kimia yang sering digunakan
teknik disinfeksi adalah kaporit, karena harganya yang murah dan
mudah didapat dan residunyaberwarna putih. Aplikasinya juga mudah
karena dapat menggunakan peralatan sederhana atau menggunakan
dosingpump. Bentuk bahan kaporit ini ada yang berbentuk gas,
cairan, butiran ataupuntablet. Pemakaian kaporit, harus
menggunakan takaran/dosis yang tepat karenasisa klor mudah
bersenyawa dengan bahan bahan organik seperti amoniak yang
akanmembentuk senyawa trihalomethane atau chloroform yang
bersifat karsinogenik
~ Koagulasi, Jika dalam keadan tertentu, jika sumber airlimbahnya
terlalu banyak bahan tersuspensi perlu dikendalikan dengan
menambahbahan koagulan untuk mengurangi konsentrasinya.
Bahan koagulan yang sering dipakai antara lain:
· Tawas, atau aluminium sulfat (Al2SO4),sering digunakan
karena endapan floknya berwarna putih dan menurunkan sedikitpH
air. Didalam proses koagulasi seringditambahkan bahan alkali dan
pembantu koagulan untuk mempercepatterbentukya flok (gumpalan)
didalam air.Pengaturan dosis tawas dilakukandengan jar test
sederhana, dosis yang dipakai yaitu : 20 mgr/l, 40 mgr/l, 60
mgr/l , 80 mgr/l dan 100 mgr/l . Dengan membandingkan
tingkatkekeruhan setelah pembubuhan tawas maka diketahui dosis
tawas yang cocok
· PAC, Poly Aluminium chloride, jugabanyak digunakan
sebagai koagulan dalam pengolahan karena lebih efisien daripada
tawas, namunharganya lebih mahal dari bahan koagulan lain.
· Koperas atau Ferro sulfat (Fe2SO4),banyak digunakan dalam
pabrik yang banyak mengandung zat warna, harganya murah,namun
menghasilkan residu berwarna kuning.
C. PENGOLAHAN SECARA BIOLOGIS
Didalam pengolahan air limbahruimah sakit yang banyak
dibahasteknologinya adalah pengolahan secara biologis, yaitu
menggunakan jasamikroorganisme pengurai untuk merombak atau
menguraikan bahan organik yang adadidalam air limbah untuk
pertumbuhan, pembentukan sel baru atau pemeliharaankehidupannya .
Didalam habitatnya, mikroorganisme pengurai yang mampu
melakukansintesa biokomia adalah bakterigolongan heterotropic.
Golongan bakteriini sangat dominan sebagai bakteri pengurai dan
mudah berkembang biak, karakternya dapat dijelaskan sebagai
berikut :
1).Bakteri Anaerob,
Bakteri anaerob yaitu bakteri yangmempunyai habitat kehidupan
dalam suasana tanpa oksigen, bakteri ini mulai dilirik oleh para
ahli untukmemperbaiki kinerja IPAL rumah sakit yang konventional
yang memerlukan pasokanbanyak oksigen (energi), seperti
pengolahan dengan sistem lumpur aktif(activated sludge) .
Pada awalnya bakteri anaerob inidigunakan untuk mengolah air
limbah asal peternakan yang banyak kandungan bahanorganic guna
menghasilkan gas methane (CH4). Konsep penggunaan bakteri anaerob
dalam sistem pengolahan air limbahrumah sakit karena :
· Efisiensi penyisihan terhadapbahan bahan pencemar cukup
tinggi, hampir semua parameter utama dalam air limbah seperti :
BOD, COD, TSS, NH4, dan MBAS (detergen) dapatditurunkan secara
bermakna.
· Tidak memerlukan tambahanenergi dari luar , yaitu energi
listrik untuk menggerakkan peralatan mesinseperti pengaduk atau
blower , sehingga dapat menekan biaya dalam sistempengolahan
pengolahan air limbah.
· Tidak memerlukan tambahannutrien dari luar, karena
kebutuhan pasokan nutriennya rendah maka sudah cukup dari bahan
organik yang ada didalamair limbah, bakteri anaerobik juga
mempunyai yield sel yang rendah, makaproduksi lumpur hasil
penguraiannya sangat sedikit.
Secara skematis proses penguraiananaerobic yang menggunakan jasa
bakteri pengurai dapat digambarkan sebagai berikut: