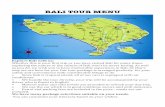Buletin BPTP Bali Volume 19 Nomor 1 (April) Tahun 2021
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Buletin BPTP Bali Volume 19 Nomor 1 (April) Tahun 2021
CONTENT CAN BE QUOTED WITH THE SOURCE
Bul. Tek & Info Pertanian Vol. 19 No. 1 Hal. 1 - 79 DenpasarApril 2021
ISSN: 1693 - 1262
BULETIN TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERTANIANISSN: 1693 - 1262
Penanggung JawabKepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Dewan RedaksiDr. drh. I Made Rai Yasa, MP (Sistem Usaha Pertanian)
Ir. I Ketut Kariada, M.Sc. (Budidaya Pertanian)Dr. Ir. Ni Wayan Trisnawati, M.M.A. (Teknolongi Pasca Panen)Dr.I Gusti Komang Dana Arsana,SP.M.Si (Budidaya Pertanian)
I Ketut Mahaputra, SP.MP (Sosial Ekonomi Pertanian)Ir. Ida Ayu Parwati, MP (Sistem Usaha Pertanian)
drh. Nyoman Suyasa, M.Si (Sistem Usaha Pertanian)I Nyoman Adijaya, SP.MP (Budidaya Pertanian)
Hadis Jayanti, SP.MP (Hama dan Penyakit Tanaman)
Mitra BestariProf. Ir.M Sudiana Mahendra, MAppSc, Ph.D (Ilmu Lingkungan)
Prof.Ir.I Made S. Utama, M.S,Ph.D (Teknologi Pascapanen Hortikultura)Prof. (Riset) Dr. I Wayan Rusastra, M.S (Agroekonomi dan Kebijakan Pertanian)
Prof. (Riset) Dr. Ir. Rubiyo, M.Si (Pemuliaan dan Genetika Tanaman)
Redaksi Pelaksanadrh. I Nyoman SugamaM.A Widyaningsih, SP
drh. Berlian Natalia, M.SiAnella Retna Kumala Sari, MP
Rachmad Dharmawan, S.Pt. M.Pt.
Alamat RedaksiBalai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) - Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali 80222PO.BOX 3480
Telepon/ Fax: (+62361) 720498email: [email protected]
website: http://www.bali.litbang.deptan.go.id
Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian memuat pemikiran ilmiah, hasil – hasil kelitbangan,atau tinjuan kepustakaan bidang pertanian secara luas yang belum pernah diterbitkan pada
media apapun, yang terbit tiga kali dalam satu tahun setiap bulan April, Agustus, dan Desember
BULETIN TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERTANIAN
Volume 19 Nomor 1 April 2021
ISSN : 1693 - 1262
TABLE OF CONCENT
DIVERSIFIKASI PANGAN LOKAL UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGANPADA MASA PANDEMI COVID-19
Yennita Sihombing .............................................................................................................. 1-12
KARAKTER MORFOLOGI DAN POTENSI PISANG LOKA JONJO (Musa acuminata)ENDEMIK SULAWESI BARAT
Muhtar, Marthen P. Sirappa, dan Ketut Indrayana ............................................................ 13-18
KERAGAAN PERTUMBUHAN DAN HASIL SERTA POLA PANEN DUA VARIETAS CABAILOKAL DI DESA ANTAPAN, KECAMATAN BATURITI, KABUPATEN TABANAN
I Nyoman Adijaya .............................................................................................................. 19-25
KOMPOSISI SUSU AWAL LAKTASI KAMBING PERANAKAN ETAWAH BERDASARKANPERIODE LAKTASI DAN LITTER SIZE DENGAN PEMELIHARAAN INTENSIF
Rachmad Dharmawan dan Puguh Surjowardojo ............................................................. 26-32
PELUANG PEMANFAATAN LIMBAH KULIT BUAH KAKAO SEBAGAI PAKANTERNAK SAPI DI DESA CANDIKUSUMA, KECAMATAN MELAYA, JEMBRANA
M.A Widyaningsih ............................................................................................................. 33-38
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI MELALUI TEKNOLOGI PERBENIHAN KOPIROBUSTA KLON BP 308 DI LOKASI TTP DESA SANDA KABUPATEN TABANAN
I Made Sukadana, I Wayan Sunanjaya, I Nengah Duwijana ............................................ 39-45
PERILAKU PESERTA TEMU TEKNIS INOVASI PERTANIAN TENTANG PENGOLAHANBAWANG MERAH
I Wayan Alit Artha Wiguna, I Gusti Made Widianta,Ni Ketut Sudarmini, Agung Prijanto .................................................................................. 46-56
POTENSI LIMBAH JAGUNG MANIS MENDUKUNG KETERSEDIAAN PAKAN TERNAKSAPI BALI DI KECAMATAN KLUNGKUNG, KABUPATEN KLUNGKUNG
Ni Luh Gede Budiari, I Nyoman Adijaya dan I Nyoman Sutresna .................................... 57-63
TINGKAT EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN WARU (Hibiscus tiliaceus) TERHADAPPARASIT GASTROINTESTINAL PADA SALURAN PENCERNAAN KAMBINGPERANAKAN ETTAWAH (PE) DI DESA SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM
I Wayan Sudarma dan A.A.N. Badung Sarmuda Dinata .................................................. 64-72
TINGKAT SERANGAN HAMA UTAMA DAN HASIL PANENBEBERAPA VARIETAS JAGUNG DI LINGKUNGAN SAWAH TADAH HUJAN
Ni Made Delly Resiani dan I Nengah Duwijana ................................................................ 73-79
1
DIVERSIFIKASI PANGAN LOKAL UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGANPADA MASA PANDEMI COVID-19
Yennita Sihombing
Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi PertanianJl. Tentara Pelajar No. 10, Bogor, 16114E-mail: [email protected]
Submitted date : 18 Januari 2021 Approved date : 8 Pebruari 2021
ABSTRACT
Local Food Diversification to Support Food Security in the Covid-19 Pandemic Time
The impact of the Covid-19 pandemic has disrupted various aspects of life from health, social, economy,and various others, in most parts of the world. One of the main problems is with regard to food security whichis currently very busy in public discussion as a consequence of the COVID-19 pandemic which is increasinglywidespread, especially in Indonesia.Food is a pillar primary for the needs of the Indonesian people, thereforethe importance of special attention from many parties in an effort to meet the needs of the community and onhow to anticipate food security during the Covid-19 pandemic.Objective of this paper is to analyze accomplishmentof local food consumption diversification and to formulate strategyfor local food based food consumptiondiversification.The results showed that there was reduction in local food consumption including that in theregionswith localfood based staple food pattern previously. Development of local food diversification as part offoodsovereignty implementation should be conducted together by all stakeholders. Some efforts to take areformulatingand implementing policy strategy related to optimizing land potential use and local food consumptionhabit, as wellas development of local food production, industry and local food consumption.
Keywords: Food security, local food diversification
ABSTRAK
Dampak dari pandemi covid-19 telah mengganggu berbagai aspek kehidupan mulai kesehatan, sosial,ekonomi dan beragam lain sebaginya, di sebagian besar belahan dunia. Salah satu persoalan utamanya adalahberkenaan ketahanan pangan yang saat ini menjadi sangat ramai dalam perbincangan publik sebagaikonsekuensi dari pandemi covid-19 yang semakin meluas khususnya di Negara Indonesia. Pangan adalahsuatu tonggak utama bagi kebutuhan masyarakat Indonesia, maka dari itu pentingnya perhatian khusus daribanyak pihak dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan tentang bagaimana untuk mengantisipasiketahanan pangan di masa pandemic covid-19.Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis capaian diversifikasikonsumsi pangan lokaldan menyusun strategi pengembangan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal.Hasil kajian menunjukkan telah terjadi penurunan konsumsi panganlokal, termasuk di wilayah yang sebelumnyamempunyai pola pangan pokok berbasis pangan lokal.Pengembangan diversifikasipangan lokal sebagai bagianuntuk mewujudkan kedaulatan pangan hendaknya dilakukan oleh semua kalangan. Upaya tersebut dapatdilakukan dengan menyusun dan implementasi strategi kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan potensilahan dan kebiasaan mengkonsumsi pangan lokal, serta pengembangan produksi, industri, dan konsumsipangan lokal.
Kata kunci: Ketahanan pangan, diversifikasi pangan lokal
Diversifikasi Pangan Lokal Untuk Mendukung Ketahanan PanganPada Masa Pandemi Covid-19 | Yennita Sihombing
2 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
PENDAHULUAN
Pangan dan ketahanan pangan merupakanhal yang sangat penting bagi ketahanan nasionalsuatu bangsa. Ketahanan pangan bagi suatunegara merupakan hal yang sangat penting,terutama bagi negara yang mempunyaipenduduk sangat banyak seperti Indonesia.Mengacu pada kondisi nyata sekarang ini, duniakhususnya Indonesia mengalami krisis panganyang disebabkan karena ketersediaan lahan danproduksi pangan yang tidak mampumengimbangi pesatnya pertambahan penduduk.Implikasinya adalah produksi pangan harusmenjadi semakin banyak, akan tetapi lahanpertanian semakin sempit. Hal ini menyebabkankenaikan harga pangan karena kelangkaanpangan dan semakin bertambahnya penduduk,sehingga menjadi pemicu kenaikan tingkat inflasi.
Pengertian pangan lokal dalam konteksnasional mengacu pada Undang-UndangNomor18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan),adalah makanan yang dikonsumsi olehmasyarakat setempat sesuai potensi dankearifan lokal,yaitu sumber daya pangan danbudaya makan setempat. Disebut pangan lokalapabila diproduksi dengan mengoptimalkansumberdaya setempat dan dikonsumsi secaraturun-temurun oleh masyarakat setempat, baikdalam bentuk pangan segar maupun yang telahdiolah sesuai budaya dan kearifan lokal, danmenjadi makanan khas daerah setempat.Beberapa contoh jenis pangan lokal antara lainsagu buat masyarakat Papua dan Maluku,jagung untuk penduduk Nusa Tenggara Timurdan Madura, singkong bagi keluarga di Jawabagian selatan dan Lampung. Pangan lokal yangbelum dimanfaatkan secara intensif yaituberbagai jenis umbi-talas, ganyong, hanjeli, danhotong.
Upaya pencapaian ketahanan pangan tidakhanya mengandalkan upaya peningkatanproduksi. Diperlukan rencana aksi strategis untukusaha pencapaian ketahanan pangan. Strategiyang diperlukan adalah alternatif lain dari upayapeningkatan produksi yang telah dan masih terusdilakukan, diantaranya meningkatkan usahapenyimpanan air (water storage), efisiensi danreprioritas penggunaan air yang ada, diversifikasipangan dan investasi tanaman yang toleransalinitas, cekaman kelebihan dan kekurangan air(Nusifera, 2013).
Virus corona (covid-19) merupakan penyakitmenular yang tengah menyebar dan sekurang-
kurangnya telah menginfeksi 1 juta orang dansebanyak 90% negara di dunia telah menjadikorban.Segala aspek pencegahan danpenanggulangan telah dilakukan oleh berbagaipihak di seluruh dunia terhadap pandemi yangterjadi sejak bulan Maret 2020 sampai dengansaat ini.yang menyokong kehidupan masyarakat,termasuk diantaranya sektor pertanian.Sektorpertanian menjadi sorotan karena memiliki kaitanerat dengan ketahanan pangan nasional. Padamasa pandemi yang sulit seperti sekarang iniketahanan pangan menjadi sesuatu yang harusdiupayakan untuk menghindari krisis panganyang seakan menghantui Indonesia (Wulandanidan Wiwin, 2020).
Pandemi Covid-19 telah menyebabkanterganggunya kegiatan perekonomian di semualini usaha, termasuk sektor pertanian. Salah satudampak yang harus diantisipasi terkait dampakCovid-19 adalah ketersediaan pangan bagiseluruh rakyat. Gerakan Ketahanan Pangan(GKP) yang diperkenalkan oleh KementerianPertanian di tengah ancaman virus corona saatini harus didukung oleh semua pihak, khususnyapetani dan penyuluh sebagai ujung tombak danpenggerak sektor pertanian. salah satu cara yangditempuh untuk mewujudkan ketahanan pangandi tengah pandemi Covid-19 adalah melaluidiversifikasi pangan lokal. Diversifikasi panganlokal berkonotasi pada adanya pilihan bahanpangan lokal sebagai alternatif untuk mengurangiketergantungan pada satu jenis pangan yangdominan. Fakta selama ini, jenis pangan dominandi Indonesia adalah beras. Oleh sebab itu,diversifikasi pangan menjadi salah satu strategimencapai ketahanan pangan (Setiawan, 2012).
Dari uraian tersebut, tujuan penulis dalammenulis makalah ini adalah untuk menganalisiscapaian diversifikasi pangan lokal dalammendukung ketahanan pangan di tengahpandemi covid-19.
METODOLOGI
Bahan literatur yang digunakan dalampenulisan makalah ini adalah beberapa referensiyang berasal dari hasil penelitian, kajian, danulasan dari beberapa tulisan yang kemudiandirangkum menjadi suatu karya tulisan ilmiah.Pengkajian dilakukan dengan menggunakanMetoda Desk Research, data yang digunakanadalah data sekunder yang berasal dari berbagaisumber yaitu; Badan Penelitian dan
3
Pengembangan Kementerian Pertanian, PSEKP,jurnal dan sumber lainnya yang mendukung.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pola Konsumsi Pangan
Pangan diartikan sebagai segala sesuatuyang berasal dari sumber hayati dan air baik yangdiolah maupun yang tidak diolah.Pangandiperuntukkan bagi konsumsi manusia sebagaimakanan atau minuman, termasuk bahantambahan pangan, bahan baku pangan, danbahan-bahan lain yang digunakan sebagaiproses penyiapan, pengolahan dan pembuatanmakanan atau minuman. Komoditas panganharus mengandung gizi yang terdiri ataskabohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineralyang bermanfaat bagi pertumbuhan dankesehatan manusia.
Pola konsumsi pangan merupakan suatususunan dari berbagai bahan dan hasilolahannya yang biasa dimakan seseorang yangtercermin dalam jumlah, jenis, frekuensi, dansumber bahan makanan.Pola konsumsi panganseseorang maupun kelompok masyarakat dapatdievaluasi menggunakan Pola Pangan Harapan(PPH). Pola pangan harapan merupakan suatupegangan kecukupan pangan yang diwujudkandalam susunan beragam pangan denganmasing-masing tingkat kontribusinya untukmengetahui lebih jauh kecukupan ketersediaanenergi juga disertai dengan komposisi panganyang beragam, bergizi dan seimbang (Indiako,et al., 2014). Menurut Thenu (2013) bahwa polakonsumsi masyarakat bervariasi (pola makancampuran). Pola campuran adalah suatu tradisiyang sudah terpola dan merupakan bentukantisipasi terhadap berbagai resiko seperti :musim, daya beli masyarakat dan ketersediaansumber lauk pelengkap. Berdasarkan polapenanganan pangan tersebut, maka masyarakattetap bertahan dalam kondisi apapun di wilayahkepulauan.
Budaya pangan masyarakat Indonesiasecara dinamis terus berubah. Pada tahun 1950-an, mayoritas masyarakat Indonesiamengandalkan pada pangan lokal yang variatifyang ada di berbagai daerah. Masyarakat Malukudan Papua memiliki budaya pangan yangberkaitan dengan sagu dan umbi-umbian,sementara masyarakat Nusa Tengara Timur
(NTT) mengandalkan jagung. Tiga dekadekemudian, pada tahun 1980an, terutama setelahIndonesia mencapai swasembada beras (tahun1984), budaya pangan bergeser ke beras.Program pembangunan pertanian yang masif(revolusi hijau) yang berorientasi pada padi/beraspada masa Orde Baru ternyata juga diikuti olehperubahan pola pangan pokok masyarakat.Konsumsi pangan pokok beras terus meningkatdan sejak awal tahun 2000an hampir seratuspersen masyarakat Indonesia mengonsumsiberas (Ariani, 2016). Gejala ini sering disebut‘berasisasi’ dan menandai munculnya budayapangan nasional (Simatupang, 2012).
Masalah kekurangan pangan pada dasarnyadisebabkan karena penduduk tidak memilikiakses terhadap sumber-sumber produksi panganseperti tanah, air, input pertanian, modal danteknologi; tingkat daya beli masyarakat untukmembeli konsumsi pangan yang rendah, tidaktersedianya produksi pangan lokal, ketahananpangan penduduk yang rendah. Selainitu, tidakadanya perhatian dari semua pihak untukmempertahankan sumber pangan lokal (jagung,umbi-umbian: singkong dan ketela rambat,pisangdan talas) yang semakin hari semakin hilangkarena produksi pangan lokal semakin berkurangserta infrastruktur untuk menunjang produksipangan lokal tidak tersedia (Warsilah, 2011).
Elizabeth, (2011) menyatakan bahwa telahterjadi pergeseran pola konsumsi panganmasyarakat non beras menjadi beras sepertiyang terjadi di Madura, Maluku, NTT,Ambon, danKawasan Indonesia Timur lainnya. Bahkan diMaluku yang pada awalnya mengkonsumsi sagusebagai bahan pangan pokok, telah beralihsekitar 90-100% menjadi beras. Hal ini sejalandengan hasil penelitian Hardono, (2014) dimanaperubahan pola pangan masyarakat yangterjadipada beberapa lokasi seperti Nusatenggara, Papua, Maluku dan Sulawesi adalahdari dominan pangan lokal seperti jagung, umbi-umbian, dan sagu berubah ke arah pola pangannasional (beras), kemudian berubah ke arah polapangan internasional berbasis gandum.
Sagu menjadi sumber konsumsi yang cukupbaik dalam penyeimbangan pola konsumsisehari-hari khususnya bagi masyarakatIndonesia bagian Timur.Kebiasaanmengkonsumsi sagu pada acara ritual maupunseremonial mengindikasikan bahwa polakonsumsi masyarakat mulai berubah darisebelumnya primer menjadi sekunder.Masyarakat tidak lagi mengkonsumsi sagu
Diversifikasi Pangan Lokal Untuk Mendukung Ketahanan PanganPada Masa Pandemi Covid-19 | Yennita Sihombing
4 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
terbantahkan dengan fenomena bahwa dalamritual maupun seremonial makan berbahanpokok sagu selalu dihidangkan sebagai salahsatu konsumsi favorit (Breen, et al., 2018).
Ariani, (2010) menyatakan bahwa polakonsumsi pangan pokok masyarakat Indonesiamasih berupa pola pangan tunggal yaitu beras.Ketergantungan untuk mengonsumsi berasberdampak negatif pada masyarakat itu sendiriserta perekonomian negara. Tingginya imporberasIndonesia untuk memenuhi permintaansehingga sangat berpengaruh pada stabilitasperekonomian negara.
Badan Ketahanan Pangan (BKP)menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhirmasyarakat Indonesia memiliki pola konsumsipangan pokok kombinasi beras dan terigu.Berdasarkan parameter kontribusi energimasing-masing jenis pangan sumberkarbohidrat, BKP (2012) menyimpulkan bahwamasyarakat di 27 (dari 33) provinsi memiliki polakonsumsi pangan pokok beras-terigu.Selanjutnya di sejumlah provinsi tertentumasyarakat memiliki kombinasi beras danpangan lokal: provinsi NTT dengan beras-jagung,Gorontalo dengan beras-jagung-terigu, MalukuUtara dengan beras-terigu-ubikayu, Maluku danPapua Barat dengan beras-terigu-ubikayu-sagu,dan Papua dengan beras-terigu-ubi kayu-ubijalar-sagu.
Pangan Lokal
Pangan lokal adalah makanan yangdikonsumsi masyarakat setempat sesuai potensidan kearifan lokal.Produk pangan lokal Indonesiasangat melimpah. Produk pangan lokal sangatberkaitan erat dengan budaya masyarakatsetempat. Oleh karena itu, produk-produk inikerap kali juga menyandang nama daerah,seperti, dodol garut, jenang kudus, gudek jokya,dan lain-lain.Beraneka ragam dan jumlah yangsangat besar dari produk pangan lokal tersebutsangat berpotensi dalam mewujudkankemandirian pangan nasional. Terwujudnyakemandirian pangan suatu daerah atau negara,dengan sendirinya akan mempercepattercapainya ketahanan pangan nasional.
Pangan pokok lokal tradisional yangmudahtumbuh dan dapat ditanam relatif tanpapemeliharaan yang spesifik ini tetap dapatditemukan dalam pola konsumsi sehari-hari,akan tetapi tidak sebagai pangan pokok
melainkan sebagai pangan kudapan,yangdinikmati pada sore hari atau disela-sela waktumakan utama. Penyajiannya antara lain dengancara digoreng (singkong goreng, ubi jalar goreng,dan bakwan jagung); direbus (singkong, ubi jalar,jagung, kentang, uwi, dan gembili); dikolak(singkong dan ubi jalar), disayur (kentang danjagung); dibuat gethuk dan tape: singkong(Fadhilah, 2013).
Namun demikian, hingga saat ini, produkpangan lokal belum mampu menggeser berasdan tepung terigu yang mendominasi makanandi Indonesia. Salah satu penyebabnya adalahrendahnya inovasi teknologi terhadap produkpangan lokal. Walaupun mulai ada kreasiterhadap produk pangan lokal, namun jumlahnyamasih dirasakan sangat terbatas seperti CassavaVruitpao (Bakpao yang terbuat dari singkong),steak kampung Mucuna Crspy (steak berbahanbaku kara benguk), rasi (nasi dari singkong),brownies dari singkong, dan lain-lain. Sehinggapangan lokal belum mampu menarik minatkonsumen untuk mengkonsumsinya. Di sisi lain,di era globalisasi saat ini, permintaan konsumenakan produk pangan terus berkembang.Konsumen tidak hanya menuntuk produk panganbermutu, bergizi, aman, dan lezat, namun jugasesuai selera atau bahkan dapat membangkitkanefek gengsi atau berkelas bagi yangmengkonsumsinya. Oleh karena itu, inovasi ataukreasi terhadap produk pangan tidak hanyaterfokus pada mutu, gizi, dan keamanan semata.Namun aspek selera konsumen (preferensi) jugapatut dipertimbangkan (Yuliatmoko, 2011).
Salah satu cara yang dapat ditempuh dalammelakukan kreasi terhadap produk pangan lokalagar sesuai dengan preferensi konsumen saatini adalah melakukan inovasi terhadap nama,bentuk, trend penyajian, dan kemasan dariproduk pangan lokal. Sebagai misal memberinama, bentuk, trend penyajian, dan kemasanproduk pangan lokal dengan nama, bentuk, carapenyajian, dan kemasan yang lagi trend atausedang digandrungi oleh konsumen ataumasyarakat. Hasil uji penerimaan konsumen danpemasaran produk dipasaran menunjukkanproduk ini menarik minat konsumen terutamakalangan mahasiswa
Ketahanan Pangan
Pembangunan bidang ketahanan pangan diIndonesia diarahkan untuk meningkatkan
5
ketahanan pangan dan melanjutkan revitalisasipertanian dalam rangka mewujudkankemandirian pangan,peningkatan daya saingproduk pertanian, peningkatan pendapatanpetani, serta kelestarian lingkungan dansumberdaya alam, namun pada bagian tertentu,ketahanan pangan sulit untuk dipenuhi ketikapersoalan konsumsi masyarakat menjadi terbalikdengan perencanaan dalamsebuah prosespenciptaaan masyarakat yang berketahananpangan (Umanailo, 2018).
Ketahanan pangan memiliki 5 unsur yangharus dipenuhi, diantaranya: (1) Berorientasipada rumah tangga dan individu, (2) Dimensiwaktu setiap saat pangan tersedia dan dapatdiakses, (3) Menekankan pada akses panganrumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomidan sosial, (4) Berorientasi pada pemenuhan gizi,dan (5) Ditujukan untuk hidup sehat danproduktif.
Ketahanan pangan minimal mengandungunsur pokok, yaitu ketersediaan pangan,aksesibilitas masyarakat, dan stabilitas hargapangan. Suatu negara belum dapat dikatakanmempunyai ketahanan pangan yang baik jikasalah satu dari unsur tersebut tidak dapatterpenuhi,. Walaupun pangan tersedia cukup ditingkat nasional dan regional, tetapi jika aksesindividu untuk memenuhi kebutuhan pangannyatidak merata, maka ketahanan pangan masihdikatakan rapuh. Salah satu hal yang sangatpenting dalam upaya memperkuat strategiketahanan pangan adalah distribusi pangansampai ke pelosok rumah tangga perdesaan.
Faktor-faktor yang mempengaruhiketahanan pangan secara sederhana bisadibedakan antara yang bersifat fisik dan non-fisik.Faktor-faktor fisik merupakan aset yang memilikinilai ekonomis, misalnya tanah, rumah, danternak.Sementara faktor-faktor yang bersifat non-fisik, berupa nilai sosial maupun kultural yangdimiliki oleh komunitas yang bersangkutan.Salahsatu aspek yang bersifat non-fisik yangberpengaruh terhadap tingkat ketahanan pangansebuah komunitas adalah sistem atau bentukkelembagaan sosialnya yang dipengaruhi olehmodal sosial yang dimiliki masyarakat (Warsilah,2013).
Bagi Indonesia upaya yang harus ditempuhuntuk memantapkan ketahanan panganmencakup aspek kuantitatif maupun kualitatif.Pola konsumsi pangan penduduk negeri inisangat terdominasi beras, padahal
kebergantungan yang berlebihan terhadap satujenis komoditas sangatlah rawan. Dari sisikonsumsi, mengakibatkan penyempitanspektrum pilihan komoditas yang mestinya dapatdimanfaatkan untuk pangan. Dari sisi produksijuga rawan karena: (i) pertumbuhan produksipadi sangat ditentukan oleh ketersediaan airirigasi yang cukup sedangkan air irigasi semakinlangka, (ii) laju konversi lahan sawah kenonsawah sangat sulit dikendalikan, dan (iii)kemampuan untuk melakukan perluasan lahansawah (new construction) sangat terbatas karenabiaya investasi semakin mahal, anggaran sangatterbatas, dan lahan yang secara teknis-sosial-eionomi layak dijadikan sawah semakinberkurang(Nusifera, 2013).
Berdasarkan kasus pandemic covid-19dapat di ambil kesimpulan bahwa ketahananpangan suatu negara terancam apabila terjadikrisis pangan global yang berdampak kepadaharga dan suplai pangan di pasar internasional,dan selanjutnya negara tersebut memilikipendapatan per kapita yang rendah, persentasepemasukan untuk pangan diatas 35 persen, sertaketidakmampuan pengampu kebijakanketahanan pangan untuk beradaptasi dengangejolak global (Alfiky et al., 2012).
Pangan Lokal dan Ketahanan Pangan
Pangan lokal merupakan produk panganyang telah lama diproduksi, berkembang dandikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompokmasyarakat lokal tertentu. Umumnya produkpangan lokal diolah dari bahan baku lokal,teknologi lokal, dan pengetahuan lokal pula. Disamping itu, produk pangan lokal biasanyadikembangkan sesuai dengan preferensikonsumen lokal pula. Sehingga produk panganlokal ini berkaitan erat dengan budaya lokalsetempat. Karena itu, produk ini sering kalimenggunakan nama daerah, seperti gudekjokya, dodol garut, jenang kudus, beras cianjur,dan sebagainya (Hariyadi, 2010).
Hasil studi Kementerian Lingkungan Hidupseperti yang disitir oleh Pusat Ketersediaan danKerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan(2012) menyebutkan bahwa Indonesia sedikitnyamemiliki 100 spesies tanaman biji-bijian, umbi-umbian, sagu, penghasil tepung dan gulasebagai sumber karbohidrat. Namun, hanyabeberapa jenis pangan sumber karbohidrat sajayang dikenal secara luas dan dimanfaatkan untuk
Diversifikasi Pangan Lokal Untuk Mendukung Ketahanan PanganPada Masa Pandemi Covid-19 | Yennita Sihombing
6 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
dikonsumsi secara intensif seperti padi, jagung,ubi kayu, ubijalar, sagu, dan lainnya. Bahkan,beberapa jenis pangan tersebut telah tergantikanoleh beras dan gandum.
Ketahanan pangan menurut Wahid, (2014)adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumahtangga yang tercermin dari tersedianya panganyang cukup, baik jumlah maupun mutunya,aman, merata, dan terjangkau.Kebijakan yangditurunkan oleh pemerintah dalam aplikasinyabelum banyak mendukung pangan lokal sebagaipangan pokok melainkan berfokus pada pangannasional yang pada prakteknya tiap-tiap daerahberbeda.
Sumberdaya lokal termasuk di dalamnyapangan lokal erat kaitannya dengan ketahananpangan. Ketahanan pangan yang dikembangkanberdasarkan kekuatan sumberdaya lokal akanmenciptakan kemandirian pangan, yangselanjutnya akan melahirkan induvidu yangsehat, aktif, dan berdaya saing sebagaimanaindikator ketahanan pangan. Di samping itu, jugaakan melahirkan sistem pangan dengan pondasiyang kokoh. Dengan demikian, ketahananpangan perlu didukung dengan pondasikemandirian pangan. Kaitan erat antara panganlokal dengan ketahan pangan dapat dilihat darihubungan antara kemandirian pangan denganketahanan pangan sebagaimana diilustrasikanoleh gambar 1 (Hariyadi, 2010).
Ketersediaan pangan bagi masyarakatpetani diperoleh melalui pengetahuan lokal yangdimiliki oleh masyarakat untuk mengolah sumberdaya lokal yang tersedia. Proses pengolahansumber daya alam didasarkan pada kemampuandan selera petani dalam mengakses sumberdaya lokal yang dimiliki. Kearifan lokal sebagaisumber pemenuhan kebutuhan pangan rumahtangga tercermin dari tersedianya stok pangansepanjang tahun. Hal ini dijelaskan olehSopamena et al., (2017) bahwa kearifan lokalsebagai pemenuhan kebutuhan pangan rumahtangga dengan menggunakan strategi dalampengolahan. Strategi yang digunakan dalammengolah komoditas pertanian menjadi produkyang tahan lama sehingga pangan tetap tersediasampai musim tanam berikutnya denganberdasarkan pada pengetahuan lokal setempatseperti mengolah jagung menjadi sereal, produklain juga seperti sinole.
Di sisi lain, pangan lokal atau pangantradisional dapat berperan sebagai survivalstrategi bagi masyarakat golongan ekonomilemah dalam sistem ketahanan pangan. Polapangan tradisional dapat menjadi pelengkapmakanan pokok selain beras, Adanyapenggunaan bahan lokal yang biasanya lebihterjamin ketersediaanya sebagai makanan pokokyang murah dan dapat dijangkau olehmasyarakat setempat, berdampak pada
Gambar 1. Hubungan kemandirian pangan dengan ketahanan pangan
7
penambahan pendapatan riil rumah tangga.Menurut Wahid, (2014) terdapat hubungan yangtidak dapat terpisahkan antara kearifan lokal danketahanan pangan. Hal ini disebabkan untukmewujudkan ketahanan pangan nasionalbasisnya adalah ketahanan pangan daerah danketahanan pangan daerah sendiri berbasis padakearifan lokalnya. Oleh karena itu kearifan lokalmemiliki peranan penting dalam mendukungketahanan di pulau-pulau kecil serta kearifanlokal masing-masing daerah berbeda.
Rawan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19
Pandemi Covid-19 tidak hanya berpengaruhpada kondisi sosial, ekonomi dan budayasemata, tetapi juga berpengaruh hingga kekedaulatan pangan. Kerawanan pangan menjadiancaman yang paling nyata. Sebab, adakemungkinan pandemi Covid-19 bisa menyebarke desa-desa karena ada perpindahan orang darizona merah Covid-19 di kota-kota, menuju kedesa. Dengan minimnya ketersediaaninfrastruktur di desa, maka Covid-19 dapatmengancam para petani yang menjadi produsenpangan terbesar (Abdullah, 2020).
Covid-19 mengganggu sistem panganIndonesia. Ketenagakerjaan di bidang pertaniandiperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar4,87 persen, sedangkan produksi pertaniandomestik akan menyusut sebesar 6,2 persen.Impor akan turun sebesar 17,11 persen danharganya diperkirakan akan naik sebesar 1,20persen dalam jangka pendek dan sebesar 2,42persen pada 2022. Dengan berkurangnyapasokan dalam negeri dan dari impor,kekurangan pangan dan inflasi harga makananberpotensi besar terjadi.
Data terkini menunjukkan sektor pertaniantelah mengalami kontraksi. Pada Februari 2020,penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanianmenurun sebesar 60 ribu orang atau sekitar 0,42persen dibandingkan dengan tahun lalu.Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2020menunjukkan bahwa sektor pertanian hanyamampu tumbuh 0,02 persen secara tahunan.Meskipun demikian, sektor petanian masih cukuppotensial untuk menjadi tumpuan dalammendorong pertumbuhan ekonomi. Secarakuartalan, pertanian masih sanggup tumbuh 9,46persen (BPS, 2020).
Dalam masa pandemi ini pemerintah telahmemberlakukan kebijakan PSBB (Pembatasan
Sosial Berskala Besar) di beberapa daerah,masyarakat juga diminta untuk mengurangikontak fisik dan melakukan pekerjaan dari rumah.Hal ini dapat berpengaruh pada produksi,distribusi, dan juga konsumsi pangan. Saranauntuk melakukan distribusi pangan menjaditerbatas sehingga terjadi kurangnya produktifitaspangan. Selain itu, dengan pola hidupmasyarakat yang berubah, otomatis permintaanmasyarakat sebagai konsumen pangan jugaberubah. Hal ini dapat mengakibatkan perubahanharga-harga pada produk pangan. Meskipunjumlah produksi pangan saat ini tidak mengalamibanyak perubahan dan masih dapat dikatakanaman, permasalahan krisis pangan tetap dapatterjadi kedepannya. Permasalahan yang palingbesar terjadi pada distribusi pangan. Denganadanya pembatasan-pembatasan, distribusipangan menjadi lemah. Akibatnya, stok pangantidak merata di semua daerah. Ada daerah yangmengalami defisit dan ada pula yang mengalamiproduksi berlebih (Anonimous, 2020).
Kementerian Pertanian memiliki agendayang bersifat jangka pendek, menengah danpanjang dalam menghadapi pandemi Covid-19.Agenda jangka pendek adalah dengan menjagastabilitas harga pangan dan membangun bufferstock. Agenda jangka menengah diwujudkandengan melanjutkan padat karya pasca Covid-19, diversifikasi pangan lokal, membantuketersediaan pangan di daerah defisit, antisipasikekeringan, menjaga semangat kerja pertanianmelalui bantuan saprodi dan alsintan, mendorongfamily farming, membantu kelancaran distribusipangan, meningkatkan ekspor pertanian, danmemperkuat Kostratani. Sementara agendajangka panjang (permanen) dilakukan, yaitudengan mendorong peningatan produksi 7% pertahun dan menurunkan kehilangan hasil (losses)menjadi 5%.
Peran Pangan Lokal di Tengah PandemiCovid-19
Sumber pangan Indonesia tidak hanyabergantung terhadap pertanian monokultur berassaja melainkan dapat berasal dari berbagaisumber pangan lokal yang tidak kalah bergizidibandingkan beras seperti ubi, singkong,memiliki kandungan gizi untuk sehat 100gramnya mengandung : energi 154 kilokalori,karbohidrat 36,8 gram, vitamin C 31miligram, besi 1,1miligram, kalsium 77 miligran,
Diversifikasi Pangan Lokal Untuk Mendukung Ketahanan PanganPada Masa Pandemi Covid-19 | Yennita Sihombing
8 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
dan protein 1 gram. Ubi jalar mengandung energi151 kilo kalori,karbohidrat 35,4 gram, vitamin C31 miligram, besi 0,7miligram, kalsium 29miligram dan protein 1,6 gram.Tanaman sagumengandungenergi 355 kilo kalori, fosfor 167miligram, besi 2,2 miligram,kalsium 91 miligramdan protein 0,6 gram (Wandik,2020)
Empat prinsip pangan lokal sebagaiketahanan pangan, pertama, pangan bersifatlokal yang berarti budidayanya menggunakanbenih unggul dan plasma nutfah pangan lokal,serta pengambilannya dari hutan dan laut denganmenerapkan kearifan lokal. Pengelolaan daur-hidup pangan memanfaatkan cara dan teknologilokal, dengan mendayagunakan modal sosialsetempat, dan pengkonsumsianyamengutamakan keberagaman pangan berbasissumber daya pangan setempat. Kedua, lestariyang bermakna alami, berkelanjutan, keragamanpangan, varietas lokal, dan menyimpan lebihsedikit limbah pangan, serta ramah lingkungan.Ketiga, pangan juga memenuhi aspekkesehatan, seperti; bergizi, berkualitas, tidakdiproses berlebihan, segar, bersih, aman, tidakmengandung pengawet yang tidak alami.Keempat, pangan memiliki nilai keadilan, dimanaia tersedia dalam jumlah cukup saat dibutuhkan,berada dalam jarak dekat dengan konsumen,dapat dibeli dengan harga terjangkau, dan wajarsepanjang rantai nilai pangan, sertaketersedianya beragam, bermutu, aman, sehat,segar, dan sesuai nilai budaya
PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)mengingatkan bahwa pandemic Covid-19mengancam pasokan pangan global karenapembatasan negara. Penguatan sistem panganlokal penting untuk mendukung ketahananpangan di masa pandemic Covid-19. Tradisi polaproduksi dan konsumsi pangan pendudukIndonesia yang beragam, sesuai kekayaansumber daya lokal yang ditunjangkeanekaragaman pangan merupakan kunciketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
Pangan lokal memiliki peran sangat pentingdalam konstruksi sistem pangan nasionalkhususnya ditengah pandemi Covid-19.Pertama, pangan lokal sebagai sumberkeragaman bahan pangan untuk pencapaianketahanan pangan dan gizi keluarga. Denganberaneka jenis tanaman dan ternak sumberkarbohidrat, protein, vitamin dan mineral; dalamkombinasi komposisi pola pangan yang tepatakan mendukung penyediaan pangan yang
sesuai dengan Pola Pangan Harapan (PPH),yaitu pola pangan yang menunjukkankeseimbangan komposisi gizi makanan.Istimewanya pola pangan ini berbasis sumberdaya, budaya, dan kearifan lokal, sehinggapencapaian ketahanan pangan dan gizimasyarakat setempat berdasarkan kemandirianpangan.
Kedua, berbagai jenis makanan lokal yangmerupakan hasil kreativitas budaya dan kearifanlokal meningkatkan ketersediaan beragammakanan yang bergizi. Misalnya, komposisipangan dalam makanan pempek, gudeg, danBubur Manado mengandung sumber energi danprotein asal nabati dan hewani. Contoh lain, ikankayu, tiwul, Dodol Garut merupakan hasil kearifanlokal, yang dengan menggunakan teknologiolahan pangan dapat memperpanjang shelf-lifedari bahan pangan yang dalam bentuk bahanasalnya cepat rusak atau busuk.Ketiga, panganlokal dapat menjadi katup pengaman dalammenjaga pasokan pangan bagi keluarga petanidi pedesaan pada saat terjadi guncanganterhadap ketersediaan pangan. Pada saat pasartidak dapat melayani kebutuhan panganmasyarakat dengan baik akibat terhentinyaakses fisik karena bencana atau terganggunyaakses ekonomi karena lonjakan harga, panganlokal yang ditanam petani di pekarangan, kebun,atau ladang selalu ada yang siap untukdipanen.Keempat, usaha pangan lokalberpotensi sebagai pencipta kesempatan kerjadan tambahan pendapatan rumah tangga, sertapenggerak ekonomi daerah. Pemanfaatan lahanpekarangan atau kebun di sekitar rumahmenciptakan kesempatan kerja bagi ibu rumahtangga, menyediakan tambahan bahan pangansehingga mengurangi pengeluaran rumahtangga untuk pangan, dan bila dilaksanakansecara sungguh-sungguh sebagai usahaberkelompok sehingga mencapai skala usahadapat menghasilkan tambahan pendapatan bagirumah tangga. Pada tahapan ini penggunaanbibit unggul, teknologi budi daya, dan teknologipengolahan pangan diperlukan untuk menjaminefisiensi dan produktivitas serta kualitas produk.Hasil akhirnya, ketahanan pangan dan gizikeluarga dapat lebih baik (Suryana, 2020).
Ditengah pandemi Covid-19 pengembanganpangan lokal berbasis kearifan lokal masyarakatadat adalah solusi unsur mencegah terjadinyakrisis pangan. Oleh sebab ituinformasi gizipangan lokal yang tumbuh subur dan tersedia
9
cukup melimpah dikebun-kebun milik masyarakatadat,dapat ditanam dengan mudah, tanpamembutuhkan perawatan dan media tanamanyang harus dimodifikasi dengan teknologipertanian yang canggih, menjadi kekuatansurplus pangan, jika diterapkan secara seriusoleh pemerintah berdasarkan karakteristikwilayah dan budaya pangan nusantara(Tehupeiory, 2020).
Diversifikasi Konsumsi Pangan Lokal
Diversifikasi pangan merupakan upayapenting untuk menghindari ketergantunganmasyarakat pada suatu kelompok pangantertentu. Diversifikasi pangan mencakup dimensigizi dan juga ketahanan pangan. Dalam aspekgizi, diversifikasi pangan berarti adanya utilisasipangan yang memenuhi kebutuhan dankecukupan gizi untuk hidup sehat dan produktif;sedangkan, dalam dimensi ketahanan pangan,diversifikasi pangan berarti ketidak tergantunganpada pangan utama dimana hal ini bisamembawa pada kerentanan ketahanan pangan(Astuti et al., 2015).
Diversifikasi pangan yang dimaksudkanbukan untuk menggantikan beras sepenuhnya,namun mengubah dan memperbaiki polakonsumsi masyarakat supayalebih beragamjenis pangan denganmutu gizi yang lebih baik.Diversifikasi produksi pangan dilakukan denganmeningkatkan produksi pangan pokok denganbahan dasar yang lebih bermacam-macam,misalnya dengan memproduksi makanan pokokdengan berbahan pangan lokal (Hariyadi, 2010).
Masalah yang masih menjadi kendala dalammengembangkan diversifikasi konsumsi panganselain terletak pada dukungan produksi anekapangan dalam negeri, juga terletak padapemahaman mengenai gizi oleh masyarakat,tingkat pendapatan masyarakat, dan tak kalahpentingnya adalah masalah budaya.Tingginyapenghargaan masyarakat terhadap beras sangatbertolak belakang dengan pandangan terhadappangan pokok lokal tradisional sumberkarbohidrat yang lainseperti singkong, jagungdan sagu, yang diposisikan sebagai bahanpangan inferior (Hanafie, 2010).
Empat perspektif perlunya mewujudkanpercepatan diversifikasi pangan menurut Arianidan Pitono (2013), yaitu: (1) sebagai komitmenIndonesia untuk menurunkan prevalensi rawanpangan/ kelaparan sesuai kesepakatan MDGs;
(2) peningkatan produksi pangan, terutamaberas, ke depan akan semakin sulit; (3)permintaan pangan akan terus meningkatsebagai dampak dari peningkatan jumlahpenduduk dan perubahan struktur penduduk kearah penduduk usia produktif serta sebagaidampak pertumbuhan ekonomi; (4) kekayaanKeanekaragaman Hayati dan Potensi ProduksiPangan Lokal yang memungkinkan untukmelakukan diversifikasi produksi dan konsumsipangan.
Diversifikasi pangan lokal dapat ditempuhmelalui, (a) pengembangan diversifikasi panganlokal berbasis kearifan lokal dan berfokus padasatu produk pangan, (b) pemanfaatan panganlokal secara masif misalnya, ubi kayu, sagu,pisang, jagung, kentang, sorgum dan lainnya, (c)pemanfaatan lahan pekarangan dan marjinalmelalui program pekarangan pangan lestari(Fatamorgana, 2020).Faktor yang secaralangsung maupun tidak langsung menjadikekuatan pengembangan diversifikasi panganyaitu: (1) potensi lahansubur masih banyak, (2)masih tersedia lahankering dan marginal, (3)produksi pangan lokal meningkat, (4) hargapangan cenderung meningkat, (5) ragam jenispangan lokal banyak,dan (6) adanya ragampengolahan pangan lokal spesifik wilayah(Hardono, 2014).
Diversifikasi konsumsi pangan lokal sangatberperan dalam kaitannya dengan aspek gizi,kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia,baik menyangkut pertumbuhan fisik,perkembangan mental, kecerdasan, maupunproduktivitas kerja.Diversifikasi konsumsi panganlokal merupakan beranekaragamnya jenispangan yang dikonsumsi penduduk mencakuppangan sumber energi dan zat gizi lain sehinggamemenuhi kebutuhan akan pangan dan zat giziyang seimbang, baik ditinjau dari segi kualitasmaupun kuantitasnya.Diversifikasi konsumsipangan juga harus diimbangi dengan diversifikasiproduksi pangan dan diversifikasi ketersediaanpangan. (Satmalawati dan Falo, 2016).Diversifikasi konsumsi pangan lokal disampingmerupakan implementasi dari pola konsumsipangan lokal dalam menu makanan sehari-hari,juga dapat diartikan sebagai kemampuanmeminimalkan konsumsi pangan lokal tertentuterutama pada masa-masa sulit. Yang lebihpenting adalah mengangkat citra pangan pokoklokal tradisional agar dapat bersaing danbersanding dengan beras.
Diversifikasi Pangan Lokal Untuk Mendukung Ketahanan PanganPada Masa Pandemi Covid-19 | Yennita Sihombing
10 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
Strategi Diversifikasi Pangan Lokal
Upaya yang dilakukan untuk pengembangandiversifikasi pangan dilakukan denganmemanfaatkan potensi lahan dan kebiasaanmengkonsumsi pangan lokal di masyarakat,sebagai berikut: (1) memanfaatkan potensi lahandan kebiasaan mengkonsumsi pangan lokaluntuk mendukung penekanan diversifikasipangan dalam UU Pangan; (2) memanfaatkanpotensi lahan dan kebiasaan mengkonsumsipangan lokal dalam rangka mengantisipasimerebaknya rumah makan dengan panganmodern/ import; (3) meningkatkan kebijakanproduksi dan industri pangan lokal dalam rangkamendukung penekanan diversifikasi pangandalam UU Pangan; (4) meningkatkan kebijakanproduksi dan industri pangan lokal agar mampumengantisipasi merebaknya rumah makandengan pangan modern/import (Hardono, 2014).
KESIMPULAN
Seiring dengan menguatnya adopsi danpraktik budaya pangan nasional dan global olehmasyarakat Indonesia, budaya pangan lokalyang telah lama dipraktikkan oleh masyarakattidak hilang begitu saja.Masyarakat Indonesiamemiliki traditional food system yang diwariskandari generasi kegenerasi di berbagai daerah.Halini ditandai oleh masih adanya produksi, distribusidan konsumsi pangan lokal, meskipun dalamskala dan praktiknya yang terbatas.
Potensi ketersediaan pangan lokal Indo-nesia memang sangat melimpah. Namundemikian, hingga saat ini kontribusinya dalammendukung ketahanan pangan masih sangatrendah. Hal ini antara lain disebabkan olehkurangnya inovasi teknologi terhadap produkpangan lokal tersebut sehingga produk yangdihasilkan belum mampu menarik minat konsu-men pangan di Indonesia. Untuk itu, diversifikasipangan lokal yang meliputi inovasi teknologiproduk pangan lokal mutlak harus dilakukan,bukan saja terhadap aspek mutu, gizi, dankeamanan, tetapi yang tidak kalah penting jugaharus menyentuh aspek preferensi konsumen.Khususnya di bidang keanekaragaman pangan,diversifikasi pangan lokal diharapkan dapatberperan dalam meningkatkan nilai tambahproduk pangan lokal, sehingga produk panganlokal yang dihasilkan menarik minat konsumen.
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, S. 2020. Ancaman rawan pangan ditengah pandemi Covid-19. https://kedaulatan pangan.org/ancaman-rawan-pangan-di-tengah-pandemi-covid-19/.Diakses 21 Januari 2021.
Alfiky, A.,Kaule,G., and Salheen, M. 2012.Agriculture fragmentation of the nile delta; amodeling apporoach to measuring agri-cultural land deterioration in Egyptian NileDelta. Procedia Environmental Sciences, 14,79-97. https://Doi.Org/10.1016/j.Proenv.,n.d..Diakses 21 Januari 2021.
Anonimous. 2020. Ketahanan pangan Indonesiadi masa pandemi. https://www.umy.ac.id/ketahanan-pangan-indonesia-di-masa-pandemi.html.Diakses 21 Januari 2021.
Anonimous. 2020. Gerakan ketahanan panganpada masa pandemi Covid-19. http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/covid-19/program-kegiatan/367-gerakan-ketahanan-pangan-pada-masa-pandemi-covid-19.Diakses 21 Januari 2021.
Ariani M. 2010. Diversifikasi panganpokokmendukung swasembada beras.ProsidingPekan Serealia Nasional. ISBN:978-979-8940-29-3.
Ariani, M. dan J. Pitono. 2013. Diversifikasikonsumsi pangan: kinerja dan perspektif kedepan. hal. 216-245. Dalam M. Ariani, K.Suradisastra, N.S. Saad, R. Hendayana, danE. Pasandaran (Eds.). Diversifikasi Pangandan Transformasi Pembangunan Pertanian.Badan Penelitian dan PengembanganPertanian. IAARD Press. Jakarta.
Ariani, M. 2016. Pergeseran konsumsi panganlokal, suatu keprihatinan. dalam panganlokal: budaya, potensi dan prospekpengembangan. Jakarta: IAARD Press.
Astuti, R.D., Sujarwo dan K. Hidayat. 2015. Perankelembagaan lokal dalampengembangandiversifikasi pangan. Agrise, 15(3):136-146.
Badan Ketahanan Pangan. 2012. Direktoripengembangan konsumsi pangan. BadanKetahanan Pangan. Jakarta
BPS. 2020. Keadaan ketenagakerjaan IndonesiaFebruari 2020, No. 40/05/Th. XXIII, 05 Mei2020. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
11
BPS. 2020. Pertumbuhan ekonomi IndonesiaTriwulan I-2020, No. 39/05/Th. XXIII, 5 Mei2020. Badan Pusat Statistik. Jakarta
Breen, F., Coveney, J., Anne, C., and Hartwick,P. 2018. A literaturescoping review of eatingpractices and food environments in 1 and 2person households in the UK, AustraliaandUSA, pp. 126
Dewi, G.P. dan A.M. Ginting. 2012. Antisipasikrisis panganmelalui kebijakan diversifikasipangan. Jurnal Ekonomi dan KebijakanPublik, 3(1):65-78.
Elizabeth, R. 2011. Strategipencapaiandiversifikasi dankemandirian pangan: antaraharapandan kenyataan. IPTEK TANAMANPANGAN, 6(2):230-242.
Fadhilah, A.2013.Kearifan lokal dalammembentuk daya pangan lokalkomunitasMolamahu Pulubala Gorontalo. Al-Turâa,19(1):23-37
Fatamorgana, P.B. 2020. Ketahanan pangan dimasa pandemi Covid-19. https://infokes.dinus.ac.id/2020/11/10/ketahanan-pangan-di-masa-pandemi-covid-19/.Diakses 9Februari 2021.
Hanafie, R. 2010. Peran pangan pokok lokaltradisionaldalam diversifikasi konsumsipangan. J-SEP, 4(2):1-7.
Hardono, G. S. 2014. Strategipengembangandiversifikasi panganlokal.Jurnal AnalisisKebijakan Pertanian, 12(1):1-17.
Hariyadi, P. 2010. Penguatan industri penghasilnilai tambah berbasis potensi lokal: perananteknologi pangan untuk kemandirianpangan. Jurnal PANGAN, 19(4):295-301.
Indiako, M.I.S.D.V. R.H.Ismono dan A.Soelaiman. 2014. Studi perbandingan polaalokasi lahan, pengeluaran berasdan polakonsumsi pangan antara petani ubi kayu didesa pelaksanadan non pelaksana programMP3L di Kabupaten Lampung Selatan.JIIA,2(4):331-336.
Nusifera, S. 2013.Mencapai ketahanan panganmelalui diversifikasi dan eksplorasi panganalternatif. https://www.unja.ac.id/2013/04/11/mencapai-ketahanan-pangan-melalui-diversi f ikasi-dan-eksplorasi-pangan-alternatif/. Diakses 21 Januari 2021.
Satmalawati, E. M., dan Falo, M.2016.Diversifikasi konsumsi pangan pokokberbasis potensi lokal dalam mewujudkanketahanan pangan di Kecamatan InsanaBarat Kabupaten Timor Tengah Utara NTT.Prosiding Semnas Hasil Penelitian “InovasiIPTEKS Perguruan Tinggi UntukMeningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”(pp. 250–268). Denpasar.
Simatupang, P. 2012. Restorasi budaya pangannusantara sebagai penopang kedaulatanpangan nasional. dalam pangan lokal:budaya, potensi dan prospekpengembangan. Jakarta: IAARD Press.
Sopamena J. F, Sukesi. K, Hidayat. K, Sugiyanto.2017. “Local Wisdom and Food Resiliencein Selaru Island Community Of MalukuProvince”. 5 (2) :170-172.
Suryana, A. 2020.Pangan lokal untuk ketahananpangan dan gizi masyarakat pada masapandemi Covid-19. http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/covid-19/opini/417-pangan-lokal-untuk-ketahanan-pangan-dan-gizi-masyarakat-pada-masa-pandemi-covid-19#!/ccomment.Diakses 9 Februari2021.
Tehupeiory, A. 2020. Kearifan lokal masyarakathukum adatdi pulau Ambon (Maluku)dalammewujudkan kedaulatan pangan dimasapandemi (Covid-19). Buku Kearifan LokalMasyarakat Hukum Adat dalam MewujudkanKedaulatan Pangan di tengah PandemiCovid-19. Lembaga Studi Hukum Indonesia.ISBN.978-623-94988-1-8. Jakarta. Hal. 399-420.
Thenu. S. F. W. 2013 “Model pengembanganagribisnis jagung untuk mendukungketahanan pangan berbasis gugus pulau diKabupaten Maluku Barat Daya ProvinsiMaluku”. Disertasi. Bogor : Institut PertanianBogor.
Umanailo, M.C.B. 2018. Ketahanan pangan lokaldan diversifikasi konsumsi masyarakat: Studipada Masyarakat Desa WaimangitKabupaten Buru. Jurnal Sosial-EkonomiPertanian dan Agribisnis, 12(1):63-74.
Wahid, M. A. 2014. Kearifan lokal (local wisdom)dan ketahanan pangan. Skripsi. UniversitasPadjajaran.
Diversifikasi Pangan Lokal Untuk Mendukung Ketahanan PanganPada Masa Pandemi Covid-19 | Yennita Sihombing
12 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
Wandik, W. 2020. Ketahanan pangan dimasapandemi.https://kabarpapua.co/bupati-puncak-pastikan-ketahanan-pangan-di-tengah-pandemi-melimpah/. Diakses 9Februari 2021.
Warsilah H. 2011. Penerapan kebijakanketahanan pangan bagi pencapaiankedaulatan pangan. Makalah disampaikanpada KIPNAS Tahun 2011 Diselenggarakanoleh LIPI, di Hotel Bidakara, Jakarta.
Warsilah H. 2013. Peran food habits masyarakatperdesaan pesisir dalam mendukung
ketahanan pangan:kasus Desa Bahoi danBulutui di Kabupaten Minahasa Utara. JurnalMasyarakat dan Budaya, 15(1):97-130.
Wulandani, B.R.D. dan Wiwin, A. 2020. Foodestate sebagai ketahanan pangan di tengahpandemi Covid-19 di Desa Wanasaba.Jurnal Pengabdian MasyarakatBerkemajuan, 4(1):386-390.
Yuliatmoko, W. 2011. Inovasi teknologi produkpangan lokal untuk percepatan ketahananpangan. Prosiding.Seminar NasionalFMIPA-UT 2011.
13
KARAKTER MORFOLOGI DAN POTENSI PISANG LOKA JONJO (Musa acuminata)ENDEMIK SULAWESI BARAT
Muhtar1, Marthen P. Sirappa,2 dan Ketut Indrayana3
1.2,3)Peneliti pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi BaratKompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi BaratJln. Abdul Malik Pattana Endang, Mamuju 91552
E-mail: [email protected]
Submitted date : 20 Januari 2021 Approved date : 25 Pebruari 2021
ABSTRACT
Morphological Characteristics and Potency Banana Loka Jonjo (Musa acuminata) Endemic to West Sulawesi
Banana loka Jonjo is one of the local genetic resources of West Sulawesi Province potential to be utilizedas a source of nutrition, so it needs to be characterized and developed its potential. This study aims were todetermine the morphological characteristics and potency of banana loka Jonjo in West Sulawesi. Observationwas done by survey method and interview with farmer followed by characterization using guide of bananadescriptor. The results showed that banana loka Jonjo was only found in one location, that was in Padang Bakahamlet, Rimuku village, Mamuju sub district, Mamuju district. Morpholocically banana loka Jonjo almost similarto banana loka Pere in terms of having long flat leaf shape, upright leaves, symmetrical leaf shape, spikyrounded heart shape, reddish purple outer heart color, heart position at the end of the stem and the shape offruit bunches facing upwards. Loka Jonjo is usually consumed as fresh fruit (table fruit), can also be used as aprocessed banana.
Keywords: Loka jonjo; local banana, endemic, morphological character, potential, West Sulawesi
ABSTRAK
Pisang loka Jonjo merupakan salah satu sumber daya genetik lokal Provinsi Sulawesi Barat yang berpotensiuntuk dimanfaatkan sebagai sumber gizi, sehingga perlu dikarakterisasi dan dikembangkan potensinya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakter morfologi dan potensi pisang loka Jonjo di Sulawesi Barat.Pengamatan dilakukan dengan metode survei dan wawancara dengan petani dilanjutkan dengan karakterisasimenggunakan panduan deskriptor pisang. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pisang Jonjo hanya ditemukandi satu lokasi yaitu di Dusun Padang Baka, Desa Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Secaramorfologi karakter pisang loka Jonjo mirip pisang loka Pere yaitu dengan bentuk daun panjang pipih, dauntegak, letak daun simetris, bentuk jantung bulat lonjong runcing, warna jantung bagian luar ungu kemerahan,kedudukan jantung di ujung batang dan bentuk tandan buah menghadap keatas. Pisang loka jonjo biasadikonsumsi sebagai buah segar (pisang meja), juga dapat dijadikan sebagai pisang olahan.
Kata kunci: Loka jonjo, pisang lokal, endemik, karakter morfologi, potensi, Sulawesi Barat
PENDAHULUAN
Indonesia merupakan pusat keanekara-gaman pisang, sehingga jumlah pisang liar danpisang budidaya melimpah dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Setidaknya 12 jenis
berada di Indonesia di antara 71 jenis pisang didunia dan dua jenis diantaranya, yaitu Musaacuminata Colla dan Musa balbisiana Collamerupakan nenek moyang pisang budidaya(Simmonds, 1962; Nasution, 1991; Daniells,1995; Nasution dan Yamada, 2001; Poerba,
Karakter Morfologi dan Potensi Pisang Loka Jonjo (Musa acuminata)Endemik Sulawesi Barat | Muhtar, dkk.
14 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
et.al., 2016). Di Indonesia terdapat kurang lebih230 jenis pisang khas lokal (Prabawati, 2008),beberapa keragaman pisang antara lain pisangbarangan yang berasal dari Provinsi SulawesiSelatan dan Sumatra, pisang mas, ambon lumut,pisang kapas (Jawa Barat), pisang kayu biasa(Jawa Timur) pisang ambon mandar (Bengkulu),pisang Tongkat (Maluku), pisang jarum danpisang takut api (Papua), pisang talas dan pisangtelunjuk (Kalimantan Selatan), pisang madu(Kalimantan Tengah), serta pisang raja yangditemukan hampir seluruh wilayah Indonesia(Poerba, et.al. 2016).
Indonesia juga memiliki lebih dari 200 kul-tivar pisang lokal yang belum mengalamipemuliaan atau perbaikan (Nasution, 1991;Poerba, et.al. 2016), sementara jenis pisangyang telah terdokumentasi terdiri atas 42 aksesipisang liar atau lokal, 139 aksesi pisang budidayadan 10 aksesi pisang hasil pemuliaan (Poerba,et.al. 2016), Menurut Sulistyaningsih (2013)bahwa diduga masih banyak spesies pisang lokalyang belum teridentifikasi dan terdokumentasidengan baik.
Pisang lokal di Indonesia tersebar luas mulaidari Sumatera, Jawa, Kepulauan Sunda Kecil,Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. PulauSulawesi mempunyai biogeografi yang unikkarena pulau ini terletak di kawasan Wallacea,yaitu suatu kawasan persebaran peralihan antarabenua Asia dan Australia. Selain itu, Sulawesidiketahui pula mempunyai flora dan faunaendemik yang cukup banyak (Mittermeier et al1999; Sulistyaningsih, 2013). Jenis daninfraspesifik dari marga Musa yang dilaporkanendemik di Pulau Sulawesi adalah M. celebicaWarb. dan M. acuminata Colla var. tomentosa(K.Sch.) Nasution (Nasution & Yamada 2001;Nasution, 1991; L.D. Sulistyaningsih, 2013).
Salah satu Provinsi di Pulau Sulawesi yangmemiliki sumber daya genetik khas dan memilikipotensi tinggi adalah Provinsi Sulawesi Barat.Sumber daya genetik yang ditemukan dan patutdikembangkan di daerah ini adalah pisang lokalyang diberi nama pisang loka Jonjo yang ditemu-kan di Kabupaten Mamuju. Jenis pisang ini memi-liki keunggulan dibandingkan dengan pisangtanduk dan pisang kepok yaitu rasanya manisdan ukuran cukup besar. Pisang ini juga dapatdikonsumsi dalam bentuk buah segar, digorengatau direbus dan daunnya dijadikan sebagaipembungkus aneka makanan olahan dan peng-ganti piring saat makan (Sirappa et al., 2016).
Kegiatan inventarisasi dan karakterisasiperlu dilakukan untuk mencari ciri spesifik yangdimiliki oleh tumbuhan yang digunakan untukmembedakan di antara jenis dan antar individudalam satu jenis suatu tumbuhan (Chaerani etal, 2011). Hasil inventarisasi dan karakterisasimerupakan modal untuk dipergunakan dalamkegiatan penyusunan program pemuliaan,maupun di dalam penyediaan bahan industriyang mempunyai nilai ekonomi tinggi.
Perbedaan karakter antar varietas dapatdilihat dari penampilan tanaman seperti batang,daun, bunga dan buah. Sifat atau karaktertersebut dapat dijadikan modal dalam perbaikansifat genetik tanaman (Rais, 2004). Denganmengembangkan potensi pisang lokal, makabukan hanya dapat meningkatkan kualitas pisangdan menjadikan pisang lebih bernilai ekonomi,tetapi juga dapat mempertahankan eksistensipisang lokal Sulawesi Barat sehingga terhindardari kepunahan (Ismail, 2015)
Permasalahan yang dihadapi adalah belumadanya inovasi teknologi budidaya pisang lokalsehingga produktivitas belum maksimal. Agarsumber daya genetik di daerah tersebut tidakpunah, maka perlu penanganan khusus olehsemua pihak dan perhatian dari pemerintahsetempat. Penelitian ini bertujuan untukmelakukan karakterisasi morfologi pisang lokaJonjo dan potensi pengembangannya sertapemanfaatannya oleh masyarakat KabupatenMamuju Sulawesi Barat.
METODOLOGI
Penelitian dilaksanakan pada tahun 2015 –2016 di enam Kabupaten Provinsi Sulawesi Baratyaitu Kabupaten Majene, Mamasa, Mamuju,Mamuju Tengah, Mamuju Utara dan PolewaliMandar. Kegiatan karakterisasi dan inventarisasidilakukan dengan metode survei, yaitu menga-mati beberapa varietas pisang lokal denganmemfokuskan pada varietas pisang loka Jonjoserta wawancara langsung dengan petani me-ngenai pemanfaatannya. Tanaman pisang lokalyang diinventarisasi berasal dari pekarangan danluar pekarangan serta di kebun koleksi.Pengambilan contoh mengacu pada metodeHawkes (1980) yaitu apabila populasi tanamanbanyak, maka dilakukan secara acak tetapi bilapopulasinya terbatas maka pengambilan contohdiambil dari tanaman yang dijumpai di lapang.
15
Karakterisasi dilakukan terhadap karaktermorfologi menggunakan buku panduanDescriptor of Banana dari IPGRI (1996) meliputitinggi tanaman (cm), lingkar batang (cm), jumlahanakan, warna batang, panjang daun (cm), lebardaun (cm), jumlah daun, warna daun, susunandaun, warna tepi tangkai daun, bentuk jantung,warna jantung, kedudukan jantung, panjang buah(cm), lingkar buah (cm), warna buah matang,jumlah sisir/tandan dan jumlah buah/sisir.
Analisis data dilakukan dengan mengum-pulkan dan tabulasi secara sistematis, selan-jutnya data hasil tabulasi tersebut dianalisissecara deskriptif sesuai dengan karakteristik danmorfologi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Inventarisasi
Hasil survei menunjukkan bahwa pisangloka jonjo hanya ditemukan di Dusun PadangBaka, Desa Rimuku, Kecamatan Mamuju,Kabupaten Mamuju pada posisi -2,70331 BT dan118,90452 LS dengan ketinggian 343 - 349 mdpl. Keberadaan loka Jonjo saat ini jarang dibudi-dayakan oleh petani lokal dan dikhawatirkanakan mengalami kepunahan. Pisang ini ditemu-kan ditanam di lahan kebun petani seluas 0,25ha di daerah pegunungan jauh dari pemukiman.Populasi tanaman ini tidak banyak, sekitar 12rumpun yang diusahakan oleh hanya satu petani.
Karakterisasi Morfologi Tanaman Pisang LokaJonjo
Karakterisasi morfologi merupakan prosesmencari ciri spesifik yang dimiliki oleh tumbuhanyang digunakan untuk membedakan diantarajenis dan antar individu dalam satu jenis suatutumbuhan. Jenis pisang loka Jonjo memilikikarakter yang sama dengan pisang loka pere(Heryanto dan Sirappa, 2016), yaitu tinggitanaman dan ketegakan batang dimana pisangloka Jonjo dan pisang loka pere yang berasaldari Kabupaten Majene sama-sama memilikitinggi lebih dari 2 meter. Jenis pisang inidikatakan normal karena memiliki tinggi lebih dari1 meter. Secara rinci deskripsi karakter morfologibatang tanaman pisang loka Jonjo dapat dilihatpada Tabel 1.
Tabel 1. Karakter Batang Pisang loka Jonjo
Uraian Karakter Morfologi
Tinggi tanaman 2,1 – 2,9 meterKetegakan batang TegakBentuk batang bulatWarna batang Hijau GelapWarna pangkal batang Hijau TuaLingkar batang 42 - 60 cmJumlah anakan 2 - 3Lebar tajuk 2 - 3 m
Karakteristik morfologi daun loka Jonjomenunjukkan beberapa perbedaan denganpisang mas jarum di Sulawesi Utara terutamakarakter bentuk pangkal daun, warna daunbagian bawah dan jumlah daun (Rembang danSondakh, 2015), akan tetapi memiliki kemiripandengan pisang loka pere dalam hal karakterbentuk daun, jumlah daun, letak daun, bentukpangkal daun, susunan daun, letak daun danwarna tulang daun. Menurut Tjitrosoepomo(2007) karakterisasi kualitatif morfologi warnadaun bervariasi dan umumnya berwarna hijau.Warna daun suatu tumbuhan dapat berubahmenurut keadaan tempat tumbuhnya dan eratsekali hubungannya dengan persediaan air danmakanan serta penyinaran matahari. Deskripsimorfologi daun pisang loka Jonjo secara rincitertera pada Tabel 2.
Dari karakter bentuk jantung, warna jantungbagian luar, warna jantung bagian dalam,kedudukan jantung dan bentuk tandan buahmenunjukkan kesamaan dengan pisang lokapere, akan tetapi untuk karakter warna buahmentah berbeda yaitu loka pere berwarna hijau
Tabel 2. Deskripsi Morfologi Daun Pisang loka Jonjo
Uraian Karakteristik
Bentuk daun Panjang pipihJumlah daun 5-7Panjang daun 265 cmLebar daun < 70 cmKetegakan daun tegakWarna tepi tangkai daun Ungu kemerahanBentuk pangkal daun Meruncing keduanyaWarna daun bagian atas hijauWarna daun bagian bawah Kuning kehijauanSusunan daun Selang selingLetak daun SimetrisWarna tulang daun Hijau terang
Karakter Morfologi dan Potensi Pisang Loka Jonjo (Musa acuminata)Endemik Sulawesi Barat | Muhtar, dkk.
16 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
sementara loka Jonjo berwarna hijau terang,warna buah matang juga menunjukkanperbedaan yaitu loka pere berwarna kuningterang sementara loka Jonjo berwarna kuning(Heryanto dan Sirappa, 2016). Selain itu bentukbuah loka Jonjo unik berbeda dengan loka pere
yaitu bulat, melengkung dan bagian dalam lancipsedangkan loka pere bulat, lurus dan bagianujung lancip. Karakteristik morfologi danpenampilan pisang loka Jonjo disajikan padaTabel 3, Gambar 1 dan 2.
Tabel 3. Karakterisasi Morfologi Jantung dan Buah Pisang loka Jonjo
Uraian Karakter Morfologi
Bentuk jantung Bulat lonjong runcing (Pisau bedah)Warna jantung bagian luar Ungu kemerahanWarna jantung bagian dalam Putih kekuninganKedudukan jantung Ujung batangBentuk buah Bulat, melengkung dan bagian dalam lancipPanjang buah 14-15 cmLingkar buah 13,8 cmDiameter Buah 4-4 cmWarna buah mentah hijau mudaWarna buah matang kuning terangWarna daging buah mentah kremWarna daging buah matang kuningKetebalan kulit buah TebalBentuk Tandan Buah Menghadap keatasRasa ManisJumlah sisir/tandan 5 - 8Jumlah buah/sisir 16 - 18
Gambar 1. Penampilan tanaman dan bentuk jantung pisang loka Jonjo
Gambar 2. Penampilan bentuk buah pisang loka Jonjo
17
Potensi dan Keunggulan Pisang loka Jonjo
Pisang merupakan komoditi tanamanhortikultura yang digemari oleh masyarakat danhampir ditemukan di setiap daerah karena tidaksulit untuk dibudidayakan, sebab tanaman inidalam perawatannya tidak memerlukan banyakpupuk dan dapat tumbuh atau toleran dalamlingkungan tropis termasuk Indonesia. Pisangtermasuk komoditas yang mempunyai nilaiekonomi cukup tinggi sehingga dapatmemberikan pendapatan yang cukup tinggi bagimasyarakat. Selain itu, pisang juga memilikibanyak macam dan rasa yang beragam sehinggadapat digunakan sebagai pisang meja yaitu dapatdikonsumsi dalam bentuk buah segar maupundijadikan sebagai pisang olahan, digoreng ataudirebus dan daunnya dijadikan sebagaipembungkus aneka makanan olahan danpengganti piring saat makan serta memilikikandungan gizi yang tinggi untuk menyehatkantubuh.
Provinsi Sulawesi Barat memiliki tingkatkeragaan agroekosistem yang tinggi, salahsatunya adalah pisang lokal loka Jonjo yang jikadikelola dengan baik pisang ini dapatdimanfaatkan sebagai sumber daya genetik khasSulawesi Barat dan pemenuhan kebutuhanpangan bagi petani dan masyarakat umumkarena selain rasanya yang manis, ukuran buahbesar serta penampilan unik dan menarik, pisangini juga dapat dijadikan sebagai pisang meja ataudikonsumsi sebagai pisang olahan seperti pisangrebus diberi santan (palu butung), pisang ijo danpisang yang dikeringkan lalu digoreng.
KESIMPULAN
Pisang Loka Jonjo memiliki karaktermorfologi yang khas dari daerah Sulawesi Baratmirip dengan pisang pere. Pisang loka Jonjohanya ditemukan pada satu kebun petani diDusun Padang Baka, Desa Rimuku, KecamatanMamuju, Kabupaten Mamuju. Pisang inimerupakan sumber daya genetik khas SulawesiBarat, sebagai pisang meja maupun diolahsecara sederhana sebelum dikonsumsi. Potensipisang harus dikembangkan sebagai sumber gizidan pisang olahan serta perlu dilestarikansebagai sumber daya hayati lokal SulawesiBarat.
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampaikan kepadaTajuddin, Sulle Robertus, Abdullah, MuhammadRicky dan Chicilia Iriani Rayo sebagai teknisilitkayasa dari BPTP Sulawesi Barat yang telahmembantu selama pelaksanaan kegiatanpenelitian ini. Penelitian ini didanai oleh DIPABPTP Sulawesi Barat tahun 2015 – 2016.
DAFTAR ACUAN
Chaerani., Hidayatun, N. dan Utami, D.W., 2011.Keragaman Genetik 50 Aksesi PlasmaNutfah Kedelai Berdasarkan 10 PenandaMikrosatelit. Jurnal Agro Biogen Vol. 7 No.2, Balai Besar Penelitian danPengembangan Bioteknologi dan SumberDaya Genetik Pertanian.
Daniells, J., 1995. Illustrated guide to theidentification of banana varieties in the southpacific. Canberra: ACIAR.
Hawkes, J. G., 1980., Crop Genetic ResourceField Collection Manual. Dept. of PlantBiology. Univ. of Brimingham, England.
Heryanto, R. dan Sirappa, M.P., 2016. PotensiSumber Daya Genetik Pisang “Loka Pere’’Sulawesi Barat. Kompleks PerkantoranPemerintah Provinsi Sulawesi Barat : LokaPengkajian Teknologi Pertanian SulawesiBarat.
IPGRI-INIBAP/CIRAD., 1996. Disciptiors forBanana (Musa spp.). International PlantGenetic resources Institute. Rome, Italy
Ismail, A. 2015. Potensi Pisang Lokal Jawa BaratSangat Bangus. http://www.unpad.ac.id/profil/ade-ismail-sp-mp-potensi-pisang-lokal-jawa-barat-sangat-bagus/. Diaksespada tanggal 20 Oktober 2017.
Mittermeier, R.A., Myers, N., Gil, P.R., &Mittermeier, C.G., 1999. Hot spot earth’sbiologically riches and most endengaredterrestrial ecoregions. Japan. Toppan.
Nasution, R., 1991. A taxonomic study of theMusa acuminata Colla with its intraspecifictaxa in Indonesia. Memoirs of the TokyoUniversity of Agriculture Vol 32, pp. 1 – 122.
Karakter Morfologi dan Potensi Pisang Loka Jonjo (Musa acuminata)Endemik Sulawesi Barat | Muhtar, dkk.
18 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
Nasution, R. E., dan Yamada, I. 2001. Pisang-pisang liar di Indonesia. Bogor: PuslitbangBiologi LIPI.
Poerba, Y. S., Witjaksono., Martanti, D.,Handayani, T., dan Herlina., 2016. KatalogPisang Koleksi Kebun Plasma NutfahPisang. Pusat Penelitian Biologi, LembagaIlmu Pengetahuan Indonesia. LIPI Press.Jakarta.
Prabawati, S., Suyanti dan Setyabudi, D.A.,2008. Teknologi Pascapanen dan TeknikPengolahan. Balai Besar Penelitian danPengembangan Pascapanen Pertanian,Badan Penelitian dan PengembanganPertanian
Rais, S.A., 2004. Eksplorasi Plasma NutfahTanaman Pangan di Provinsi KalimantanBarat. Buletin Plasma Nutfah Vol. 10 No. 1.Badan Penelitian dan PengembanganPertanian. Departemen Pertanian.
Rembang, J. H. W., dan Sondakh, J.O.M., 2014.Karakterisasi Pisang Lokal Mas Jarum DanGoroho Di Kebun Koleksi Sumber DayaGenetik Tanaman Sulawesi Utara. ProsidingSeminar Nasional Sumber Daya GenetikPertanian.
Simmonds, N., 1962. The Evolution of theBananas. London: Longman ltd.
Sirappa, M.P., Syamsuddin, Heryanto, R.,Muhtar, dan Indrayana, K., 2016.Pengelolaan Sumberdaya Genetik TanamanSpesifik Provinsi Sulawesi Barat. LokaPengkajian Teknologi Pertanian SulawesiBarat, Mamuju.
Sulistyaningsih, L. D., 2013. Pisang-pisangan(Musaceae) di Gunung Watuwila dan daerahsekitarnya. Floribunda
Tjitrosoepomo, G., 2007. Morfologi Tumbuhan.Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.266 P. Edisi ke-14.
19
KERAGAAN PERTUMBUHAN DAN HASIL SERTA POLA PANEN DUA VARIETASCABAI LOKAL DI DESA ANTAPAN, KECAMATAN BATURITI, KABUPATEN TABANAN
I Nyoman Adijaya
Peneliti Balai PengkajianTeknologi Pertanian BaliJln. By Pass Ngurah Rai Pesanggran Denpasar,Tlp. (0361) 720498
E-mail: [email protected]
Submitted date : 8 Pebruari 2021 Approved date : 15 Maret 2021
ABSTRACT
Diversity of Growth and Results and Harvest Pattern of Two Local Chili Varietiesin Antapan Village, Sub-District Baturiti, Tabanan Districts
The research was carried out at Labak Lestari Farmer Group in Antapan Village, Baturiti District, TabananRegency from May 2020 - January 2021. The study used two local varieties of small chilies, namely LocalAntapan and Local Klungkung, each 4 plots per variety with populations of 100 plants/plot on 2 farmers sothere are 16 plots. Plants were planted at a spacing of 60 cm x 40 cm on a 1.0 m wide mound using black silverplastic mulch. The area of each plot in the treatment was 20 m x 1 m (20 m2) or 100 plants. Observations weremade on the components of plant growth, namely plant height, number of leaves and number of branches,while for yield components observed the number of fruits, fruit weight, average weight per fruit, fruit diameterand yield per plot. Red picking is done every 7 days. Agronomic data were analyzed by t-test. The analysisshowed that the local Antapan chili variety had advantages in fruit size such as fruit length, fruit diameter andweight/fruit which were higher than the local Klungkung variety. Klungkung local variety has significantly higherproductivity (370.0 g/plant) than the local Antapan variety (325.50 g/plant). The higher productivity of Klungkunglocal chili variety is supported by higher growth components such as plant height, number of leaves and numberof branches so that they produce more fruit than the local Antapan variety. The peak yield of the two localvarieties tested occurred at the 6-8th harvest with a harvest span of 119 days.
Keywords: Performance, growth, yield, two local varieties of chili
ABSTRAK
Penelitian dilaksanakan di Kelompok Tani Labak Lestari Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, KabupatenTabanan dari Mei 2020 - Januari 2021. Kajian menggunakan dua varietas lokal cabai kecil yaitu Lokal Antapandan Lokal Klungkung masing-masing 4 petak per varietas dengan populasi 100 tanaman/petak pada 2 orangpetani sehingga terdapat 16 petak. Tanaman ditanam dengan jarak tanam 60 cm x 40 cm pada guludan denganlebar 1,0 m menggunakan mulsa plastik hitam perak. Luas masing-masing petak dalam perlakuan yaitu 20 mx 1 m (20 m2) atau 100 tanaman. Pengamatan dilakukan terhadap komponen pertumbuhan tanaman yaitutinggi tanaman, jumlah daun dan jumlah cabang, sedangkan untuk komponen hasil diamati jumlah buah pertanaman, berat buah per tanaman, rata-rata berat per buah, diameter buah serta hasil per petak. Panen petikmerah dilakukan setiap 7 hari sekali. Data agronomis dianalisis dengan t-test. Hasil analisis menunjukkancabai varietas lokal Antapan memiliki keunggulan dalam ukuran buah seperti panjang buah, diameter buahdan berat/buah yang lebih tinggi dibandingkan varietas lokal Klungkung. Cabai varietas lokal Klungkung memilikproduktivitas nyata lebih tinggi (370,0 g/tan) dibandingkan varietas lokal Antapan (325,50 g/tan). Produktivitascabai varietas lokal Klungkung yang lebih tinggi didukung komponen pertumbuhan seperti tinggi tanaman,jumlah daun dan jumlah cabang sehingga menghasilkan jumlah buah lebih banyak dibandingkan varietas lokalAntapan. Puncak panen kedua varietas lokal yang diuji terjadi pada panen ke 6-8 dengan rentang panen 119hari.
Kata kunci: Keragaan, pertumbuhan, hasil, dua varietas cabai lokal
Keragaan Pertumbuhan dan Hasil Serta Pola Panen Dua Varietas Cabai LokalDi Desa Antapan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan | I Nyoman Adijaya
20 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
PENDAHULUAN
Cabai merupakan salah satu komoditasstrategis nasional yang selalu mendapatperhatian lebih. Hal ini disebabkan karena cabaisering kali menjadi komoditas sebagaipenyumbang inflasi negara. Bagi masyarakatIndonesia, cabai dapat disamakan denganmentega bagi bangsa Belanda (Sumarno 2011dalam Sayekti dan Hilman, 2015). Soetiarso etal. (2006) menyatakan pada umumnya budidayacabai banyak dilakukan oleh petani pada musimkemarau. Kendala produktivitas cabai jugasangat dipengaruhi oleh faktor musim, sehinggatidak jarang terjadi fluktuasi harga yang cukuptajam. Alif (2017) juga menyatakan harga cabaisangat berfluktuatif. Saat perubahan musim danhari raya keagamaan harga melonjak mahalakibat pasokan yang tidak stabil.
Cabai digunakan sebagai penyedapmasakan, penyedap rasa, dan penambah seleramakan sehingga masakan tanpa cabai terasatawar dan hambar. BPS Prov. Bali (2020)menyatakan rata-rata kebutuhan cabai per kapitaper bulan Bali rata-rata 220 gram, karena cabaimerupakan salah bumbu dapur yang selaludibutuhkan untuk keperluan memasak.Mengingat pentingnya peran komoditas cabaitersebut maka ditetapkan kawasanpengembangan nasional salah satunya kawasanpengembangan cabai. Desa Antapan,Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan Balimerupakan salah satu kawasan yangmengembangkan cabai kecil dan termasukdalam kawasan pengembangan cabai(Permentan, 2016). Di daerah ini petanimenggunakan cabai kecil varietas lokal yangsecara turun-temurun sudah dikembangkan,yang dikenal dengan cabai lokal Antapan.Varietas ini dominan dikembangkan oleh petanikarena sudah beradaptasi baik di lokasi. Adijayaet al. (2018) menyatakan dari hasil pengujianmenunjukkan varietas lokal Antapan memilikiadaptasi dan ketahanan yang lebih baikdibandingkan varietas unggul terutama terhadapketahanan terhadap hama penyakit. Varietaslokal Antapan memiliki ketahanan lebih baikterhadap serangan Phytoptora dibandingkandengan varietas unggul lainnya yang diuji didaerah ini.
Selain itu di Bali juga dikenal varietas lokalyang banyak dikembangkan yaitu varietas lokalKlungkung. Varietas ini banyak dikembangkan
di dataran rendah Kabupaten Klungkung danjuga di daerah lainnya. Rinaldi et al. (2019)menyatakan varietas lokal ini sangatmendominasi pertanaman cabai kecil diKabupaten Klungkung. Di lokasi pendampingandi Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkungdalam satu siklus produksi dilaporkan rata-rataproduktivitasnya cabai di tingkat petani yaitu 2-3t/ha, namun dengan penerapan PTTproduktivitas bisa ditingkatkan menjadi 5,92 t/ha(Rinaldi et al., 2000). Sedangkan Jati et al. (2019)menyatakan produktivitas cabai kecil petani diKabupaten Klungkung berkisar 5-6 ton/ha.Varietas cabai lokal Klungkung juga banyakdikembangkan di daerah lain di Bali. Adijaya etal. (2012) menyatakan benih lokal yangdikembangkan di daerah Kabupaten BulelengBarat dulunya juga berasal dari cabai lokalKlungkung. Berdasarkan hal tersebut makauntuk mengetahui keragaan dan pola produksikedua varietas lokal tersebut maka kajian inidilakukan.
METODOLOGI
Kajian dilakukan di Kelompok Tani LabakLestari Desa Antapan, Kecamatan Baturiti,Kabupaten Tabanan dari Mei 2020 - Januari2021. Kajian menggunakan dua varietas lokalcabai kecil yaitu Lokal Antapan dan LokalKlungkung dengan 8 ulangan pada 2 orangpetani sehingga terdapat 16 petak. Tanamanditanam dengan jarak tanam 60 cm x 40 cm padaguludan dengan lebar 1,0 m menggunakanmulsa plastik hitam perak. Luas masing-masingpetak yaitu 20 m x 1 m (20 m2) atau 100 tanaman.
Teknis budidaya tanaman mengacu padapenerapan SOP cabai kecil yang telah disusundi daerah ini (Adijaya et al., 2019). Pengolahantanah dilakukan dengan mencangkul/bajak atautraktor, dibuat guludan dengan lebar 1,1 m danpanjang 20 m dengan lebar selokan 0,7 m.Pemberian pupuk dasar dengan menggunakanpupuk kandang sapi terfermentasi sebanyak 200kg/are, TSP 2 kg/are, KCl 1 kg/are, dolomit 1 kg/are. Guludan ditutup mulsa plastik hitam perak.Jarak tanam yaitu 60 cm x 40 cm. Benihdipindahkan ke lapangan umur 42 hari setelahsemai (hss) setelah mendapat perlakuan inducerbunga pukul empat (BP4) pada umur 28 hss.Inducer BP4 selanjutnya diberikan setelahtanaman berumur 14 hari setelah tanam (hst).
21
Pemupukan pertama dilakukan 3 minggusetelah tanam menggunakan pupuk NPK dosis100 g + 250 ml bio urin sapi dilarutkan pada 15liter air diberikan untuk luasan 100 m2.Pemupukan selanjutnya dilakukan umurtanaman 5 minggu dengan dosis yang sama.Pemupukan ketiga umur 7 minggu dengan dosis200 g NPK + 500 ml biourin sapi dicairkan pada15 liter air. Pemupukan selanjutnya dilakukanumur 10 minggu dengan cara tugal dengan dosis5 g NPK/tanaman. Setelah pemupukan kimia inidilakukan pemupukan dengan biourin setiap 3minggu sekali dengan dosis 2 liter biourin sapidilarutkan pada 30 liter air. Umur 3 bulandilakukan pemupukan NPK dengan dosis 1 kg/100 m2 + bio urin 4 liter dilarutkan dalam 30 literair. Pemupukan berikutnya diulang setiap 1 bulansekali dengan dosis yang sama.
Pengendalian OPT menggunakanpendekatan pengendalian hama terpadu denganpenerapan budidaya tanaman sehat,pengamatan rutin dan penerapan komponenPHT seperti pengendalian mekanik, penggunaanyellow trap serta pengendalian secara kimiasesuai anjuran.
Pengamatan dilakukan terhadap komponenpertumbuhan tanaman yaitu tinggi tanaman,jumlah daun dan jumlah cabang, sedangkanuntuk komponen hasil diamati jumlah buah pertanaman, berat buah per tanaman, rata-rata beratper buah, diameter buah serta hasil per petak.Data agronomis selanjutnya dianalisis dengan t-test (Kurniawan, 2008). Pola panen keduavarietas juga diamati untuk mengetahui trend danrentang panen kedua varietas yang diuji.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Komponen Agronomi
Komponen pertumbuhan yang disajikanadalah komponen pertumbuhan pada saat
tanaman berumur 6 bulan (180 hst) denganasumsi tanaman sudah mencapai puncakpertumbuhan. Hasil analisis menunjukkanvarietas lokal Klungkung memiliki tinggi tanaman,jumlah cabang dan jumlah daun per tanamanyang nyata lebih tinggi dibandingkan varietaslokal Antapan (Tabel 1). Komponen pertumbuhanyang lebih tinggi mengindikasikanhabitustanaman semakin besar. Dengan tinggitanaman, percabangan dan jumlah daun yangsemakin banyak maka akan berpengaruhterhadap kemampuan produksi tanaman.Kemampuan tanaman untuk berfotosintesis akansemakin tinggi dengan jumlah daun yang lebihtinggi, sehingga fotosintat yang dihasilkan akansemakin tinggi. Evan (1975 dalam Darmawan etal., 2014) menyatakan meningkatnya jumlahcabang primer per tanaman berpengaruhterhadap jumlah bunga per tanaman. Semakinbanyak jumlah cabang primer maka peluangjumlah bunga yang muncul dari ketiak daun yangtumbuh pada cabang primer akan lebih banyak.
Hal ini sejalan dengan hasil penelitianSudrajat (2008) yang mendapatkan semakintinggi persentase kerusakan daun berpengaruhterhadap klorofil daun dan akan diikuti oleh hasilcabai yang semakin menurun. Lebih lanjut Li(2006) menyatakan klorofil berperan dalamproses fotosintesis tumbuhan dengan mengubahenergi cahaya dan energi kimia. Klorofil adalahunsur pokok dalam fotosintesis. Ali et al. (2014)menyatakan proses fotosintesis sangat tergan-tung pada gula yang diangkut dari daun, untukmembawanya ke proses yang membutuhkanseperti pembentukan dan pematangan buah, danakhirnya untuk ciri organoleptik buah.
Panen pertama kedua varietas yang diujitidak menunjukkan perbedaan. Panen pertamadimulai pada umur tanaman 112,00 hst. Varietaslokal Antapan memberikan komponen hasil yangnyata lebih tinggi dibandingkan varietas lokalKlungkung pada komponen hasil diameter buah,panjang buah dan berat/buah, namun varietaslokal Klungkung menghasilkan rata-rata jumlah
Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman, jumlah cabang dan jumlah daun dua varietas cabai lokal di Desa AntapanKecamatan Baturiti-Kabupaten Tabanan, Tahun 2020-2021
Varietas Tinggi tanaman (cm) Jumlah daun (helai) Jumlah cabang (cabang)
Lokal Antapan 175,00 125,70 9,60Lokal Klungkung 183,10* 160,60* 12,60*
Keterangan: * berbeda nyata
Keragaan Pertumbuhan dan Hasil Serta Pola Panen Dua Varietas Cabai LokalDi Desa Antapan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan | I Nyoman Adijaya
22 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
buah/tanaman (142,30 bh vs 87,10 bh) nyatalebih banyak sehingga menghasilkan berat buahper tanaman yang lebih tinggi (370,00 g vs325,50 g). Rata-rata berat buah per tanamantersebut berpengaruh terhadap berat buah perpetak yang dihasilkan (Tabel 3). Produktivitasvarietas Lokal Klungkung lebih tinggidibandingkan hasil pendampingan Rinaldi et al.(2000) yang dilaksanakan di KecamatanBanjarangkan, Kabupaten Klungkung denganrata-rata produktivitas 328,80 g/tanaman.
Melihat hasil tersebut maka dapat dikatakanvarietas lokal Klungkung memiliki kemampuantumbuh dan berproduksi dengan baik di lokasikajian. Hal ini terlihat dari produktivitas varietaslokal Klungkung nyata lebih tinggi dibandingkanvarietas lokal setempat. Harjadi (1979)menyatakan hasil tanaman dipengaruhi olehfaktor genetik dan adaptasinya terhadaplingkungan tumbuhnya. Semakin tinggi interaksikedua faktor tersebut maka tanaman akanmampu menghasilkan dengan lebih baik. Istiqlal
(2019) dan Syukur et al. (2012) menambahkankarakter suatu individu tidak dapat dipastikanbenar-benar terwariskan karena ekspresi visual(fenotipe) namun dipengaruhi oleh faktor genetikdan faktor lingkungan.
Rata-rata jumlah panen kedua varietas tidakberbeda nyata dengan rata-rata jumlah panen17 kali atau rentang panen 119 hari, karenapanen dilakukan setiap 1 minggu sekali. Keduavarietas memiliki fase vegetatif dan generatifyang sama yang ditandai dengan waktu panenyang bersamaan. Secara morfologis perbedaanterlihat dari habitus tanaman, ukuran buah danpanjang tangkai buah yang berbeda. Varietaslokal Antapan memiliki buah yang lebih panjang,besar dan tangkai buah yang lebih panjangdibandingkan varietas lokal Klungkung,sedangkan varietas lokal Klungkung memilikihabitus tanaman yang lebih tinggi dan rimbun,jumlah buah yang lebih banyak namun memilikiukuran yang lebih kecil. Penampilan buah keduavarietas seperti gambar 1.
Tabel 2. Rata-rata jumlah buah, diameter buah, panjang buah dan panjang tangkai buah dua varietas cabailokal di Desa Antapan Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Tahun 2020-2021
Varietas Panen Jumlah buah/ Diameter Panjang Panjang tangkaipertama (hst) tan (bh) buah (cm) buah (cm) buah (cm)
Lokal Antapan 112,00ns 87,10 1,47* 5,25* 4,05*Lokal Klungkung 112,00 142,30* 1,39 4,15 3,10
Keterangan: ns tidak berbeda nyata, * berbeda nyata
Gambar 1. Perbandingan ukuran buah cabai varietas lokal Antapan dan lokal Klungkung
23
Pola Panen
Pola panen kedua varietas memiliki kesamaandengan rentang panen 17 minggu/119 hari. Beratpanen meningkat dan mencapai puncak padapanen ke 6-8 kemudian menurun pada panenberikutnya (Gambar 2). Hasil ini sejalan denganhasil penelitian Adijaya et al. (2012) yangmendapatkan hal serupa pada pola panen cabailokal di Kecamatan Gerokgak, KabupatenBuleleng dengan rata-rata produktivitasmencapai 431,23 g/tanaman. Rentang panenpada penelitian ini lebih rendah dibandingkanhasil penelitian yang dilaksanakan Adijaya danSugiarta (2013) di Kecamatan GerokgakKabupaten Buleleng yang mencapai 18 kali. Halini bisa saja disebabkan oleh perbedaan kondisi
lokasi serta waktu penanaman yang berpengaruhterhadap pertumbuhan dan produksi tanaman.
Rentang panen sangat dipengaruhi olehkondisi lingkungan. Adijaya et al. (2018)menyatakan kegagalan usahatani cabai didaerah ini karena disebabkan oleh tingginyakelembaban pada musim penghujan disaattanaman cabai mulai berproduksi, sehinggaberpengaruh terhadap serangan organismepengganggu tanaman (OPT). Hal ini sesuaidengan Rahaju dan Muhandoyo (2014 dalamRidho dan Suminarti, 2020) yang menyatakankelembaban udara terlalu tinggi akanmenyebabkan serangan penyakit pada tanamankarena kondisi lingkungan sangat optimal untukpertumbuhan jamur penyebab penyakit padatanaman.
Tabel 3. Rata-rata berat buah dan jumlah panen dua varietas cabai lokal di Desa Antapan Kecamatan Baturiti,Kabupaten Tabanan, Tahun 2020-2021
Varietas Berat/buah (g) Berat buah/tan (g) Berat buah/20 m2 (kg) Jumlah panen (kali)
Lokal Antapan 3,80* 325,50 32,53 17,00ns
Lokal Klungkung 2,70 370,00* 37,00* 17,00
Keterangan: * berbeda nyata; ns tidak berbeda nyata
Gambar 2. Pola panen per 100 tanaman dua varietas cabai lokal di Desa Antapan, Kecamatan Baturiti,Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2021
Keragaan Pertumbuhan dan Hasil Serta Pola Panen Dua Varietas Cabai LokalDi Desa Antapan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan | I Nyoman Adijaya
24 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
KESIMPULAN
Cabai varietas lokal Antapan memilikikeunggulan dalam ukuran buah seperti panjangbuah, diameter buah dan berat/buah yang lebihtinggi dibandingkan varietas lokal Klungkung.Cabai varietas lokal Klungkung memilikproduktivitas yang nyata lebih tinggi (370,0 g/tan)dibandingkan varietas lokal Antapan dengan rata-rata produktivitas 325,50 g/tan. Produktivitascabai varietas lokal Klungkung yang lebih tinggididukung oleh lebih tingginya komponenpertumbuhan seperti tinggi tanaman, jumlahdaun dan jumlah cabang sehingga menghasilkanjumlah buah yang lebih banyak dibandingkanvarietas lokal Antapan.Rentang panen keduavarietas lokal yang diuji selama 119 hari denganpuncak panen kedua varietas lokal yang diujiterjadi pada panen ke 6-8.
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampaikan kepadaseluruh anggota Kelompoktani Labak LestariDesa Antapan Kecamatan Baturiti KabupatenTabanan serta seluruh tim PengembanganKawasan Pertanian Berbasis Inovasi DesaAntapan atas dukungan dan kerjasamanyadalam persiapan, pelaksanaan sampaiselesainya penelitian ini. Terima kasih jugadisampaikan kepada Dinas Pertanian KabupatenTabanan dan PPL Wilbin Desa Antapan atasdukungannya dalam pengawalan selamapelaksanaan kegiatan lapang.
DAFTAR PUSTAKA
Adijaya, I. N., dan P. Sugiarta. 2013.Meningkatkan produktivitas cabai kecil(Capsicum annuum) dengan aplikasi bio urinsapi. Balai Pengkajian Teknologi PertanianBali.
Adijaya, N., N.L.G. Budiari, M. Sugianyar, P.A.Kertawirawan, J. Rinaldi, P.S. Elizabeth, N.Sutresna, W. Artanegara, G.A.N. Astari.2019. Model Pengembangan InovasiPertanian Bio Industri (MPIP-BI) pada LahanKering Dataran Medium Beriklim Basah.Laporan Akhir Tahun. Balai PengkajianTeknologi Pertanian Bali. 75 hal.
Adijaya, N., N.L.G. Budiari, M. Sugianyar, P.A.Kertawirawan, J. Rinaldi, P.S. Elizabeth, N.Sutresna, W. Artanegara, G.A.N. Astari2018. Model Pengembangan InovasiPertanian Bioindustri pada AgroekosistemLahan Kering Dataran Medium BeriklimBasah. Laporan Akhir Tahun. BalaiPengkajian Teknologi Pertanian Bali. 93 hal.
Adijaya, N., M.R. Yasa, K. Mahaputra, P.A.Kertawirawan, P. Sugiatra dan P.Y.Priningsih. 2012. Pengkajian pemanfaatanlimbah pada integrasi ternak sapi dantanaman di lahan kering untuk peningkatanproduktivitas lahan >15%. Laporan AkhirTahun. Balai Pengkajian Teknologi PertanianBali. 41 hal.
Ali A., A. Muzzafar, M.F. Awan, S. Din, I.A.Nasir,and T. Husnain. 2014. Geneticallymodified foods: engineered tomato with extraadvantages. Adv life sci. Vol 1(3): 139- 152.URL: http://www.als.journal.com/articles/vol1issue3/Genetically_modified_foods_engineered_tomato_ad vantages.pdf
Alif, S. M. 2017. Kiat Sukses Budidaya CabaiRawit. Bio Genesis.
BPS Prov. Bali. 2020. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan beberapa jenis bahanmakanan, 2018-2019. Badan Pusat StatistikProvinsi Bali.
Darmawan, I. G. P., I.D.N. Nyana, dan I.G.A.Gunadi. 2014. Pengaruh penggunaan mulsaplastik terhadap hasil tanaman cabai rawit(Capsicum frutescens L.) di luar musim diDesa Kerta. Jurnal AgroekoteknologiTropika, 3(3): 148-157.
Harjadi, M. S. S. 1979. Pengantar agronomi. PT.Gramedia, Jakarta.
Istiqlal, M. R. A., da M. Syukur. 2019. Keragamangenetik karakter kuantitatif pada tanamanCabai (Capsicum annuum L.). Comm.Horticulturae Journal, 1(1): 6-12.
Jati E.N., J. Rinaldi dan N. Adijaya. 2019.Peranan kegiatan kaji terap terhadappeningkatan pengetahuan dan sikappenyuluh pertanian dalam teknologipengelolaan tanaman terpadu cabai. JurnalManajemen Agribisnis 7(2): 155-160.
Kurniawan, D. 2008. Uji t 2-Sampel Independen.http://ineddeni.worpress.com
25
Li R., P. Guo, M. Baum, S. Grando, and S.Ceccareli. 2006. Evaluation of chlorophyllcontent and flouresence parameters asindicators of drought tolerance in barley. JAgric Sci in China, 5(10):751-757. DOI:10.1016/S1671-2927(06)60120-X.
Permentan. 2016. Permentan Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016. PedomanPengembangan Kawasan Pertanian.
Ridho, M. N., dan N.E. Suminarti. 2020.Pengaruh perubahan iklim terhadapproduktivitas tanaman cabai rawit (Capsicumfrutescens L.) di Kabupaten Malang. JurnalProduksi Tanaman, 8(3):304-314.
Rinaldi, J., I.B.G. Suryawan, P. Sugiarta, E.N. Jati,Y. Pujiawati, A.R. Kumalasari, M. Budiartanadan N.P.Y. Priningsih. 2020. PendampinganPengembangan Kawasan Komoditas Cabai.Laporan Akhir Tahun. Balai PengkajianTeknologi Pertanian Bali. 36 hal.
Rinaldi, J., I.B.G. Suryawan, E.N. Jati, P. Sugiarta,Y. Pujiawati, A.R. Kumalasari, M. Budiartanadan N.P.Y. Priningsih. 2019. Pendampingan
Pengembangan Kawasan Komoditas Cabai.Laporan Akhir Tahun. Balai PengkajianTeknologi Pertanian Bali. 36 hal.
Sayekti, A. L., dan Y. Hilman. 2015. Dinamikaproduksi dan volatil itas harga cabai:antisipasi strategi dan kebijakanpengembangan. Pengembangan InovasiPertanian, 8(1): 33-42.
Soetiarso, T.A., M. Ameriana, L. Prabaningrum,dan N. Sumarni. 2006. Pertumbuhan, hasil,dan kelayakan finansial penggunaan mulsadan pupuk buatan pada usahatani cabaimerah di luar musim. J. Hortikultura,16(1):63-76.
Sudarjat, S. 2008. Hubungan antara kepadatanpopulasi kutu daun persik (Myzus persicaeSulz.) dan tingkat kerusakan daun dengankehilangan hasil cabai merah (Capsicumannuum L.). Jurnal Agrikultura, 19(3): 191-197.
Syukur, M., S. Sujiprihati, dan R. Yunianti. 2012.Teknik Pemuliaan Tanaman. PenebarSwadaya. Jakarta. 348 hal.
Keragaan Pertumbuhan dan Hasil Serta Pola Panen Dua Varietas Cabai LokalDi Desa Antapan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan | I Nyoman Adijaya
26 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
KOMPOSISI SUSU AWAL LAKTASI KAMBING PERANAKAN ETAWAHBERDASARKAN PERIODE LAKTASI DAN LITTER SIZE
DENGAN PEMELIHARAAN INTENSIF
Rachmad Dharmawan1 dan Puguh Surjowardojo2
1 )Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BaliJl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar Selatan, Bali, 80222
2 )Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya MalangJl. Veteran, Ketawanggede, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur, 65145
Submitted date : 8 Pebruari 2021 Approved date : 18 Maret 2021
ABSTRACT
Early Lactation Milk Composition of Etawah Crossbred Goat Basedon Lactation Period and Litter Size By Intensive Reared
Etawah crossbred goat (PE) is one of the Indonesian indigenous dairy goat. Lactation period and littersize are factors that necesserily to be observed in evaluating the composition of the early lactation milk for PEgoats. It is expected that the composition of the early lactation milk can be used to estimate the composition ofthe milk during the lactation period. This study aimed to determine the effect of lactation period and litter size onthe nutritional content of early lactation milk in PE goats. 20 PE goats were used in the study and were groupedaccording to lactation period (2 single births and 2 twin births each). It had fulfilled the research requirements.Early lactation milking was done every day for 60 days, and analyzed by milk analyzer Lactoscan. Statisticalanalysis used a factorial randomized block design with Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). The resultsshowed that the lactation period had a significant impact on early lactation milk fat (P <0.05) except for lactose,protein, and solid non fat (P>0.05). Litter size had significant effect on all variables (P<0.05). It can be concludedthat the levels of fat, lactose, protein, solid non fat of early lactation PE goats increased in the second and thirdlactation periods. Single litter size results in betterquality of early lactation milk than twin litter sizes due togenetic and environmental factors.
Keywords: Primipara, multiparous, lactation phase, production, doe
ABSTRAK
Kambing Peranakan Etawah (PE) merupakan salah satu ternak indigenous penghasil susu. Periode laktasidan litter size merupakan faktor yang perlu diperhatian untuk mengevaluasi komposisi susu awal laktasi kambingPE. Komposisi susu awal laktasi diharapkan dapat digunakan untuk mengestimasi komposisi susu selamamasa laktasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh periode laktasi dan litter size terhadapkandungan nutrisi susu awal laktasi kambing PE. 20 ekor kambing PE digunakan dalam penelitian dandikelompokkan berdasarkan periode laktasi (masing-masing 2 kelahiran tunggal dan 2 kelahiran kembar).Ternak dalam penelitian telah memenuhi syarat penelitian. Pemerahan susu awal laktasi dilakukan setiap hariselama 60 hari, dan dianalisa dengan milk analyzer Lactoscan. Analisis statistik menggunakan RancanganAcak Kelompok Faktorial dengan Duncan’S Multiple Range Test (DMRT). Hasil penelitian menunjukkan bahwaperiode laktasi berpengaruh nyata terhadap lemak susu awal laktasi (P<0,05) kecuali laktosa, protein, danpadatan non-lemak (P>0,05). Litter size berpengaruh nyata terhadap semua variabel (P<0,05). Kesimpulandalam penelitian ini adalah kadar lemak, laktosa, protein, dan padatan non-lemak susu awal laktasi kambingPE meningkat pada periode laktasi kedua dan ketiga. Litter size tunggal menghasilkan kualitas susu awallaktasi lebih baik dibandingkan litter size kembar karena faktor genetik maupun lingkungan.
Kata kunci: Primipara, multipara, fase laktasi, produksi, induk kambing
27
PENDAHULUAN
Kambing Peranakan Etawah (PE)merupakan salah satu ternak indigenous yangdipelihara untuk menghasilkan susu sebagaiproduk utama. Produksi susu kambing PE adalah920 mL/hari(Cyrilla et al., 2015)sampai 960 mL/hari dengan rentang masa laktasi 74-268 hari(Suranindyah et al., 2020). Masa laktasi ternakperah terbagi atas 3 fase yaitu awal, pertengahandan akhir laktasi. Setelah itu, ternak perahdikering kandangkan untuk mempersiapkanmasa laktasi selanjutnya. Induk kambing PEdikering kandangkan bertujuan mempersiapkanpartus, produksi susu, dan komposisi susupascapartus(Msalya et al., 2017). Komposisisusu awal laktasi kambing PE dipengaruhi olehberbagai faktor, antara lain: 1) lama masa kering;2) periode laktasi (Zobel et al., 2015); 3) littersize, dan manajemen pemeliharaan(Suranindyah et al., 2018).
Ternak perah akan mengalami negativeenergy balance saat awal laktasi(Mehaba et al.,2019). Ini terjadi karena perombakan jaringantubuh untuk mencapai puncak produksi susu danmenyediakan zat penting penyusun susu awallaktasi (Manuelian et al., 2020). Periode laktasidan litter size merupakan faktor yang juga perlumendapatkan perhatian untuk mengevaluasikomposisi susu awal laktasi. Beberapa penelitianmenunjukkan bahwa periode laktasi dankomposisi susu memiliki korelasi yang negatif(Skibiel et al., 2013; El-Tarabany et al., 2018).Kompoisi susu pada awal laktasi diharapkandapat digunakan untuk mengestimasi komposisisusu selama masa laktasi, sehingga dapat dijadi-kan sebagai dasar manajemen pemeliharaanawal tanpa harus menunggu satu periode laktasi.
Penelitian lain juga menujukkan bahwa littersize kembar berpotensi meningkatkan kompetisidan kurangnya asupan nutrisi selama menyusuipada induk(Vas et al., 2019)yang berakibatkematian anak kambing pascapartus.Haltersebut sangat merugikan bagi pengembanganternak kambing PE, terutama peternak dengankepemilikan skala kecil. Pengetahuan tentangkomposisi susu awal laktasi juga diharapkandapat digunakan sebagai perbaikan manajemenpemeliharaan yang bertujuan meminimakanpersentase kematian anak kambing. Penelitianini bertujuan untuk mengetahui pengaruh periodelaktasi dan litter size terhadap kandungan nutrisisusu awal laktasi kambing PE.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Unit PelaksanaTeknis Pembibitan Ternak dan Hijauan MakananTernak Singosari Singosari, Malang. Kambing PEyang digunakan dalam penelitian ini adalah 20ekor dengan bobot badan 53,71±2,34kg.Kambing PE dipisahkan menjadi 5 periodelaktasi. Masing-masing periode laktasi terdapat2 induk kambing dengan kelahiran tunggal dan2 induk kambing dengan kelahiran kembar. Indukkambing PE yang digunakan dalam penelitiandalam kondisi sehat, ambing simetris,danmemiliki catatan konsepsi lengkap. Indukkambing PE ditempatkan pada kandang individuberukuran 3 m2 dan dikeringkan kandangkanselama 45 hari. Anak dan induk kambing PEdipisahkan untuk menghindari bias datapenelitian, dengan pemeliharaan ekstensifsesuai kesejahteraan ternak. Pemerahan susuawal laktasi dilakukan setiap hari selama 60 haripascapartus,dan dianalisa dengan milk analyzerLactoscan(Buditeli, 2019).Selama penelitian,induk kambing PE diberikan kebutuhan pakansesuai fase fisiologisnya (Robert, 2018).Analisisstatistik lemak, laktosa, protein, dan padatan non-lemak berdasarkan periode laktasi dan littersizedilakukan menggunakan Rancangan AcakKelompok Faktorial dengan uji lanjut Duncan’SMultiple Range Test (DMRT).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Susu adalah hasil utama pemeliharaankambing perah Peranakan Etawah (PE).Kuantitas dan kualitas susu awal laktasi kambingPE dipengaruhi genetik, umur kebuntingan (El-tarabany et al., 2018; Suranindyah et al., 2020),litter size, masa laktasi (El-tarabany and El-bayoumi, 2015; Waheed and Khan, 2013),bentuk dan ukuran ambing(Cyrilla et al., 2015),metode pemerahan (Ibnelbachyr et al., 2015)serta status kesehatan ternak. Lingkungan jugamemegang peran penting terhadap produksi dankomposisi susu (Alcedo et al., 2014; Park, 2016;Sabapara et al., 2014).Rataan masa laktasikambing PE adalah 157±41 hari yang terbagiatas 3 fase yaitu awal laktasi (7-60 hari),pertengahan laktasi (60-120 hari), dan akhirlaktasi (120-180 hari). Susu kambing tersusunatas 88% air dan 12% padatan, dengan 3,2%lemak;8,13% padatan non-lemak;0,11% kalsium;
Komposisi Susu Awal Laktasi Kambing Peranakan Etawah Berdasarkan Periode Laktasidan Litter Size dengan Pemeliharaan Intensif | Rachmad Darmawan, dkk.
28 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
0,08% fosfatdan 0,21% magnesium(Mourad etal., 2014).Kualitas susu awal laktasi padaberbagai periode dan l itter size berbedadiharapkan dapat digunakan untuk mengestimasikualitas susu pada pertengahan dan akhirlaktasi(Suranindyah et al., 2020). Kualitas susuawal laktasi kambing PE dengan berbagaiperiode laktasi dan litter size ditampilkan padaTabel 1.
Periode Laktasi
Tabel 1 menunjukkan bahwa kadar lemakinduk kambing PE meningkat pada periodelaktasi ketiga dan turun bertahap sampai periodelaktasi kelima (P<0,05). Laktosa, protein, danpadatan non-lemak meningkat pada periodelaktasi kedua dan ketiga namun analisa statistiktidak menunjukkan perbedaan signifikan(P>0,05). Sejalan dengan penelitian lain yangmengemukakan bahwa protein susu kambingperah multipara lebih baik dibandingkan ternakperah primipara(McGrath et al., 2015). Kambingperah dengan periodelaktasi ketiga, keempat,dan kelima menghasilkan kualitas susu yanglebih baik dibandingkan periode laktasi pertamadan kedua (Puppel 2019). Namun penelitian lainmengemukakan bahwa kambing dengan paritaspertama memiliki produksi susu yang tinggidengan kadar lemak dan protein lebih tinggidibandingkan kambing paritas ketiga(Mahmoudet al., 2014).Variasi hasil penelitian tersebut dapatterjadi karena pengaruh lingkungan terutamakonsumsi bahan kering untuk memulihkan skorkondisi tubuh pada fase keseimbangan energinegatif. Hal ini terlihat pada saat penelitian bahwakualitas susu awal laktasi lebih dari 45 haripascapartus mengalami peningkatandibandingkan 0-30 hari pascapartus.
Puncak produksi susu kambing PE padaumumnya terjadi pada umur 2,5-3 tahun ataupada periode laktasi kedua dan ketiga(Cyrilla etal., 2015). Laju peningkatan produksi menujupuncak produksi adalah 0,8%/hari dengan lajupenurunan 0,56%/hari(Marete et al., 2014).Penelitian lain menjelaskan bahwa produksi susuharian Kambing perah mengalami penurunansebesar 18,4% dan 31,9% pada tengah dan akhirlaktasi dibandingkan awal laktasi(El-tarabany etal., 2018). Selain itu, penurunan produksi susuharian kambing perah multipara lebih rendahdibandingkan kambing perah primipara(Oravcova et al., 2015). Hasil penelitianmenunjukkan bahwa kadar lemak susu awallaktasi kambing PE berbeda signifikan (P<0,05)kecuali laktosa, protein, dan padatan non-lemak.Namun, penelitian lain juga mengemukakanbahwa lemak, protein, padatan non-lemak,kalsium, dan fosfor susu kambing denganberbagai periode laktasi menunjukkanperbedaan signifikan (P<0,01) pada berbagaifase laktasi(El-tarabany et al., 2018).Hasilpenelitian lebih rendah dibandingkan susu awallaktasi kambing Nguni bahwa penyusun susuterdiri atas 3,80±0,06% protein, 5,70±0,08%laktosa, dan 10,30±0,16% padatan non-lemakyang lebih tinggi pada awal dan akhir laktasi(P<0,05)(Mourad et al., 2014). Variasi lemak,protein, dan padatan non-lemak dikarenakanparameter tersebut berkorelasi negatif denganpeningkatan produksi susu (Andualem et al.,2016). Penurunan lemak susu kambing lebihdisebabkan oleh peningkatan asam propionatdan penurunan asam asetat yang terdapat dalamrumen(Idamokoro et al., 2017).Laktosa susuawal laktasi kambing perah pada umumnya lebihstabil dibandingkan tengah dan akhir laktasidengan kadar laktosa tertinggi pada awal laktasi.
Tabel 1. Kualitas susu awal laktasi kambing PE pada berbagai periode laktasi dan litter size
Periode Laktasi Litter sizeParameter
1 2 3 4 5 Tunggal Kembar
Lemak % 6,43±1,89a 7,04±1,74b 7,15±1,75b 6,54±1,75ab 6,49±1,78a 6,91±1,81b 6,55±1,75a
Laktosa % 2,94±0,43 3,01±0,43 3,28±0,73 3,00±0,34 3,01±0,48 3,22±0,43b 2,87±0,53a
Protein % 2,94±0,31 3,07±0,39 3,24±0,83 2,94±0,13 2,96±0,46 3,21±0,35b 2,85±0,57a
Padatan non- 6,57±1,16 6,74±0,93 6,89±1,53 6,43±0,70 6,46±1,08 6,79±1,04b 6,44±1,11a
lemak %
a-bsuperskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan nyata (P<0.05)
29
Sebagian besar kompoisisi susu mengalamipenurunan secara bertahap dari pertengahansampai akhir laktasi kecuali laktosa yang stabilmengikuti produksi susu (P<0,05)(Mahmoud etal., 2014).
Protein susu awal laktasi kambing PE padaumumnya lebih tinggi dibandingkan akhir laktasi(Ibnelbachyr et al., 2015; Mestawet et al., 2012).Selanjutnya protein turun signifikan sampai akhirlaktasi(El-tarabany et al., 2018). Hal ini sejalandengan protein susu kambing Damaskus yanglebih tinggi selama awal laktasi dibandingkandengan pertengahan dan akhir laktasi (P<0,05).Peningkatan protein dan lemak diperkirakandisebabkan rendahnya produksi susu. Penelitianlain mengemukakan bahwa padatan non-lemaksusu awal laktasi kambing perah memilikikorelasi negatif dengan produksi susu,peningkatan produksi susu pada awal laktasitidak diikuti dengan kenaikan kualitassusu(Mestawet et al., 2012).
Litter Size
Tabel 1 menunjukkan bahwa kualitas susuawal laktasi kambing PE dengan berbagai littersize menunjukkan perbedaan signifikan(P<0,05).Sejalan dengan penelitian lain bahwakualitas susu dapat dipengaruhi berbagai faktorantara lain adalahlitter size(Antonic et al., 2013;Marete et al., 2014; Tancin et al., 2011) dan infeksipenyakit(Lopes et al., 2016). Lemak, laktosa,protein, dan padatan non-lemak susu awal laktasikambing PE pada litter size tunggal berbedasignifikan dibandingkan litter size kembar(P>0,05). Penelitian sebelumnyamengemukakanbahwa protein dan laktosa berbeda signifikanpada berbagai litter size kecuali lemak (Romeroet al., 2013). Litter size kambing pada daerahtropis tidak berpengaruh signifikan atas produksisusu tetapi berpengaruh terhadap kualitas susu(Waheed and Khan, 2013). Umumnya kambingperah dengan kelahiran kembar memproduksilebih banyak susu dengan protein yang rendahdibandingkan kelahiran tunggal(Mahmoud et al.,2014).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemak,laktosa, protein, dan padatan non-lemak susukambing PE dengan litter size tunggal lebih tinggidibandingkan litter size kembar karena terjadipeningkatan produksi susu selama masa laktasi.Sejalan dengan penelitian lain bahwa produksisusu awal laktasi mengalami penurunan dari
bulan pertama sampai akhir laktasi (P>0,05),sedangkan lemak dan protein susu mengalamipeningkatan(Mestawet et al., 2012; Oravcova etal., 2015). Lemak susu kambing PE penelitianlebih tinggi dibandingkan penelitian Suranindyahet al., (2018) bahwa kadar lemak kambing PEandalah 5,80%. Lemak susu kambingperahrelatif mengalami peningkatan mengikutifase laktasi(Ibnelbachyr et al., 2015). Lemak susuawal dan akhir laktasi secara signifikan lebihtinggi dibandingkan pertengahanlaktasi(Mestawet et al., 2012). Lemak pada awallaktasi berperan dalam menentukan komposisisusu, sedangkan lemak pada akhir laktasiberperan terhadap lipolisis yang disebabkanbakteri atau enzim pada kelenjar susu.Laktosakambing PE penelitian bervariasi antara 2,69-3,49% lebih rendah dibandingkan Cyrilla et al.,(2015) bahwa laktosa susu kambing Etawah danPeranakannya dalah 5,41%. Tren laktosamengalami penurunan signifikan pada akhirlaktasi dibandingkan dengan awal dan tengahlaktasi(El-tarabany et al., 2018; Noutfia et al.,2014). Penelitian lain menyebutkan terdapatpenurunan laktosa susu kambing pada akhirlaktasi dibandingkan awal dan pertengahanlaktasi (Ibnelbachyr et al., 2015; Idamokoro etal., 2017).
Protein susu awal laktasi kambing PEbervariasi antara 2,62-3,45% masih lebih rendahdibandingkan Suranindyah et al. (2018)bahwaprotein kambing PE adalah 3,64%. Protein,lemak dan padatan non-lemak stabil pada tahaplaktasi yang berbeda (Ibnelbachyr et al., 2015;Mahmoud et al., 2014; Mestawet et al., 2012).Protein susu awal laktasi saat penelitian lebihrendah dibandingkan kambing Kroasia danSlovenia yaitu lemak, protein, dan laktosakambing di Kroasia adalah 3,10%, 3,43%, dan4,17%sedangkan kambing di Slovenia adalah3,11%, 3,34%, dan 4,36%. Protein, laktosa, danpadatan non-lemak susu kambing Nguni padaberbagai tahap laktasi menunjukkan perbedaansignifikan (P<0,05)(Klir et al., 2015).Peningkatankandungan protein susu pada awal dan akhirlaktasi disebabkan oleh interaksi usia danlittersize.Litter size mengakibatkan komponenpenyusun susu seperti â-lactoglobulin, á-lactalbumin, á-kasein dan â-kasein menjadibervariasi(Mourad et al., 2014).Padatan non-lemak penelitian bervariasi antara 6,48-7,1%untuk liter size tunggal dan 6,11-6,8% untuk littersize kembar lebih rendah dibandingkan Cyrilla
Komposisi Susu Awal Laktasi Kambing Peranakan Etawah Berdasarkan Periode Laktasidan Litter Size dengan Pemeliharaan Intensif | Rachmad Darmawan, dkk.
30 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
et al., (2015) bahwa padatan non-lemak kambingEtawah dan peranakannya adalah 9,11%,sedangkan kambing PE dan Saanen adalah9,18%. Penelitian lain mengemukakan bahwapadatan non-lemak kambing Baladi, Draa, danNadji meningkat signifikan menjelang akhirlaktasi yang diakibatkan seiring penurunanproduksi susu(Ayadi et al., 2014; Noutfia et al.,2014). Kapasitas rumen kambing PEsaatmemasuki masa kering terdorong oleh fetus.Kapasitas rumen yang terbatas mengakibatkankonsumsi bahan menjadi kering rendah dan lajukecernaan gastrointestinal menjadi lebih cepat.Hal ini akan mengurangi kesempatan absorbsinutrisi oleh mikroba rumen, sehinggalaktogenesis susu tidak berjalan denganbaik(Banchero et al., 2015).
KESIMPULAN
Kadar lemak, laktosa, protein, dan padatannon-lemak susu awal laktasi kambing PEmengalami peningkatan pada periode laktasikedua dan ketiga. Kambing PE denganLitter sizetunggal menghasilkan kualitas susu awal laktasilebih baik dibandingkan litter size kembar karenafaktor genetik maupun lingkungan pada semuaparameter.
UCAPAN TERIMA KASIH
Kami berterimakasih kepada tim UPT PT danHMT Singosari yang telah membantumengkoleksi dan menganalisa sampel data susuawal laktasi Kambing PE.
KONTRIBUSI PENULIS
Puguh Surjowardojo berkontribusi padaperencanaan dan desain penelitian, pengum-pulan data, analisisa statistik, dan penulisanartikel. Rachmad Dharmawan berkontribusidalam pengumpulan data, dan penyuntingannaskah. Semua penulis berkontribusi sebagaikontributor utama. Semua penulis telahmembaca dan menyetujui naskah versi terakhir.
KONFLIK KEPENTINGAN
Seluruh penulis menyatakan bahwapenelitian dilakukan tanpa hubungan komersialdan finansial apa pun yang dapat mengakibatkanpotensi terjadinya konflik kepentingan
DAFTAR PUSTAKA
Alcedo, M. J., Ito, K., & Maeda, K. (2014).Creating animal welfare assessment methodfor backyard goat production in thePhilippines using stockmanship competenceas proxy indicator. International Journal ofLivestock Production, 5(10), 173–180. https://doi.org/10.5897/IJLP2014.0217
Andualem, D., Negesse, T., & Tolera, A. (2016).Milk yield and composition of grazing Arsi-Bale does supplemented with dried stringingnetlle (Urtica simensis) leaf meal and growthrate of their suckling kids. Advances inBiological Research, 10(3), 191–199. https://doi.org/10.5829/idosi.abr.2016.10.3.102187
Antonic, J., Jackuliacova, L., Uhrincat, M.,Macuhova, L., Oravcova, M., & Tancin, V.(2013). CHANGES IN MILK YIELD ANDCOMPOSITION AFTER LAMB WEANINGAND START OF MACHINE MILKING INDAURY EWES. Slovak J. Anim. Sci., 46(3),93–99.
Ayadi, M., Matar, A. M., Aljumuah, R. S., Alshaikh,M. A., & Abouheif, M. (2014). FactorsAffecting Milk Yield , Composition and UdderHealth of Najdi Ewes. International Journalof Animal and Veterinary Advances, 6(1),28–33. https://doi.org/10.19026/ijava.6.5613
Banchero, G. E., Milton, J. T. B., Lindsay, D. R.,Martin, G. B., & Quintans, G. (2015).Colostrum production in ewes/ : a review ofregulation mechanisms and of energysupply. Animal, 9(5), 831–837. https://doi.org/10.1017/S1751731114003243
Buditeli, N. (2019). Lactoscan SA Milk Analyzer.Milkotronic Ltd, 1–81.
Cyrilla, L., Purwanto, B. P., & Sukmawati, A.(2015). Improving Milk Quality for Dairy GoatFarm Development. Media Peternakan,38(3), 204–211. https://doi.org/10.5398/medpet.2015.38.3.204
31
El-tarabany, M. S., & El-bayoumi, K. M. (2015).Theriogenology Reproductive performanceof backcross Holstein  Brown Swiss andtheir Holstein contemporaries undersubtropical environmental conditions.Theriogenology, 83(3), 444–448. https://d o i . o r g / 1 0 . 1 0 1 6 / j . t h e r i o g e n o l o g y.2014.10.010
El-tarabany, M. S., El-tarabany, A. A., & Roushdy,E. M. (2018). Impact of lactation stage onmilk composition and blood biochemical andhematological parameters of dairy Baladigoats. Saudi Journal of Biological Sciences,25(8), 1632–1638. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2016.08.003
Ibnelbachyr, M., Boujenane, I., Chikhi, A., &Noutfia, Y. (2015). Effect of some non-genetic factors on milk yield and compositionof Draa indigenous goats under an intensivesystem of three kiddings in 2 years. TropicalAnimal Health and Production, 47(3), 1–7.https://doi.org/10.1007/s11250-015-0785-8
Idamokoro, E. M., Muchenje, V., & Masika, P. J.(2017). Yield and Milk Composition atDifferent Stages of Lactation from a SmallHerd of Nguni , Boer , and Non-DescriptGoats Raised in an Extensive ProductionSystem. Sustainability, 9(1000), 1–13. https://doi.org/10.3390/su9061000
Klir, Z., Potocnik, K., Autunovic, Z., Novoselec,J., Barac, Z., Mulc, D., & Kompan, D. (2015).Milk production traits from alpine breed ofgoats in Croatia and Slovenia. BulgarianJournal of Agricultural Science, 21(5), 1064–1068.
Lopes, F. C., de Paiva, A. K., Coelho, W. A. C.,Nunes, F. V. A., da Silva, J. B., Pinheiro, C.G. M. E., Praca, L. M., Silva, J. B. A., Freitas,C. I. A., & Batista, J. S. (2016). Lactationcurve and milk quality of goatsexperimentally infected with Trypanosomavivax. Experimental Parasitology Journal,167 , 17–24. https://doi.org/10.1016/j.exppara.2016.04.006
Mahmoud, N. M. A., Zubeir, I. E. M. El, &Fadlelmoula, A. A. (2014). Effect of Stage ofLactation on Milk Yield and Composition ofFirst Kidder Damascus does in the SudanJournal of Animal Production AdvancesEffect of Stage of Lactation on Milk Yield and
Composition of First Kidder Damascus doesin the Sudan. Journal of Animal ProductionAdvances, 4(3), 355–362.
Manuelian, C. L., Maggiolino, A., Marchi, M. De,Claps, S., Esposito, L., Rufrano, D.,Casalino, E., Tateo, A., Neglia, G., & Palo, P.De. (2020). Profile of Saanen Goat duringLactation with Different Mediterranean BreedClusters under the Same EnvironmentalConditions. Animals, 10(432), 2–20.
Marete, A. G., Mosi, R. O., Amimo, J. O., & Junga,J. O. (2014). Characteristics of LactationCurves of the Kenya Alpine Dairy Goats inSmallholder Farms. Journal of AnimalSciences, 4, 92–102. https://doi.org/10.4236/ojas.2014.42013
McGrath, B. A., Fox, P. F., McSweeney, P. L. H.,& Kelly, A. L. (2015). Composition andproperties of bovine colostrum: a review.Dairy Science and Technology, 96(2), 133–158. https://doi.org/10.1007/s13594-015-0258-x
Mehaba, N., Salama, A. A. K., Such, X., Albanell,E., & Caja, G. (2019). Lactational Responsesof Heat-Stressed Dairy Goats to Dietary L-Carnitine Supplementation. Animals, 9(567),1–12.
Mestawet, T. A., Girma, A., Ådnøy, T., Devold, T.G., Narvhus, J. A., & Vegarud, G. E. (2012).Milk production , composition and variationat different lactation stages of four goatbreeds in Ethiopia. Small RuminantResearch, 105(1–3), 176–181. https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2011.11.014
Mourad, G., Bettache, G., & Samir, M. (2014).Composition and nutritional value of rawmilk. Biological Sciences andPharmaceutical Research, 2(10), 115–122.https://doi.org/10.15739/ibspr.005
Msalya, G., Sonola, V. S., Ngoda, P., Kifaro, G.C., & Eik, L. O. (2017). Evaluation of growth, milk and manure production in Norwegiandairy goats in one highland of Tanzania 30years after introduction. South AfricanJournal of Animal Science, 47(2), 202–212.https://doi.org/10.4314/sajas.v47i2.12
Noutfia, Y., Zantar, S., Ibnelbachyr, M.,Abdelouahab, S., & Ounas, I. (2014).EFFECT OF STAGE OF LACTATION ON
Komposisi Susu Awal Laktasi Kambing Peranakan Etawah Berdasarkan Periode Laktasidan Litter Size dengan Pemeliharaan Intensif | Rachmad Darmawan, dkk.
32 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
THE PHYSICAL AND CHEMICALCOMPOSITION OF DRÂA GOAT MILK.African Journal of Food, Agriculture,Nutrition, and Development, 14(4), 9181–9191.
Oravcova, M., Agricultural, N., Centre, F., &Tancin, V. (2015). The effect of stage oflactation on daily milk yield , and milk fat andprotein content in Tsigai and ImprovedValachian ewes. Mljekarstvo, 65(1), 48–56.h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 5 5 6 7 /mljekarstvo.2015.0107
Park, Y. W. (2016). Production and Compositionof Milk are affected by Multivariate Factors.Advances in Dairy Research, 4(3), 3–4.h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 4 1 7 2 / 2 3 2 9 -888X.1000e131
Robert, S. (2018). Nutrient Requirements ofSheep and Goats. Alabama A&M University,1–10. https://doi.org/10.17226/20671
Romero, T., Beltrán, M. C., Rodríguez, M., Olives,A. M. De, & Molina, M. P. (2013). Shortcommunication/ : Goat colostrum quality/ :Litter size and lactation number effects.Journal of Dairy Science, 96(12), 7526–7531. https://doi.org/10.3168/jds.2013-6900
Sabapara, G. P., Kharadi, V. B., Sorathiya, L., &Patel, D. C. (2014). Housing , Health Careand Milking Management Practices Followedby Goat Owners in Navsari District ofGujarat. Journal of Agriculture andVeterinary Sciences, 1(4), 164–167.
Skibiel, A. L., Downing, L. M., Orr, T. J., & Hood,W. R. (2013). The evolution of the nutrientcomposition of mammalian milks. Journal ofAnimal Ecology, 82, 1254–1264. https://doi.org/10.1111/1365-2656.12095
Suranindyah, Y. Y., Khairy, D. H. A., Firdaus, N.,& Rochijan. (2018). Milk Production andComposition of Etawah Crossbred , Saperaand Saperong Dairy Goats in Yogyakarta ,Indonesia. International Journal of DairyScience, 13(1), 1–6. https://doi.org/10.3923/ijds.2018.1.6
Suranindyah, Y. Y., Widyobroto, B. P., Astuti, S.D., Murti, T. W., & Adiarto, A. (2020).Lactation Characteristic of Etawah CrossedBreed Goats Under Intensive Management.Bulletin of Animal Science, 44(February),22–26. https://doi.org/10.21059/buletinpeternak.v44i1.44176
Tancin, V., Macuhova, L., Oravcová, M., Uhrincat,M., Kulinová, K., Roychoudhury, S., &Marnet, P. G. (2011). Milkability assessmentof Tsigai , Improved Valachian , Lacaune andF1Crossbred ewes ( Tsigai × Lacaune ,Improved Valachian × Lacaune ) throughoutlactation. Small Ruminant Research Journal,97, 28–34. https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2011.01.007
Vas, J., Chojnacki, R. M., & Andersen, I. L. (2019).Search Behavior in Goat ( Capra hircus )Kids From Mothers Kept at Different AnimalDensities Throughout Pregnancy. Frontiersin Veterinary Science, 6(21), 1–14. https://doi.org/10.3389/fvets.2019.00021
Waheed, A., & Khan, M. S. (2013). Lactationcurve of Beetal goats in Pakistan Lactationcurve of Beetal goats in Pakistan. ArchivTierzucht, 56(89), 892–898. https://doi.org/10.7482/0003-9438-56-089
Zobel, G., Weary, D. M., Leslie, K. E., &Keyserlingk, M. A. G. Von. (2015). Invitedreview/ : Cessation of lactation/ : Effects onanimal welfare. Journal of Dairy Science, 98,8263–8277.
33
PELUANG PEMANFAATAN LIMBAH KULIT BUAH KAKAO SEBAGAI PAKANTERNAK SAPI DI DESA CANDIKUSUMA, KECAMATAN MELAYA, JEMBRANA
M.A Widyaningsih
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) BaliJl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar-Selatan, Bali 80222
E-mail : [email protected]
Submitted date : 22 Pebruari 2021 Approved date : 3 Maret 2021
ABSTRACT
The Opportunities Of Utilization Of Shells Of Cocoa Pods Waste As A Feed Of Beef Cattlein Candikusuma Village, District Melaya, Jembrana
Indonesia is the world’s third largest cocoa producer after Ivory Coast and Ghana with productivity andquality is still low. Increased production and productivity of cocoa is generally followed by problems, includingthe handling of waste in the form of cocoa shells (rind) cocoa reached 73.77% of the weight of the cocoa fruitfresh. Cocoa waste has not been widely used; although in some circumstances have the potential as animalfeed as well as raw materials for composting. Melaya sub-district, Jembrana has extensive the masses cocoaplantations in 2014 reached 1384.40 hectares with a population of of cattle reached 19 517 tail. Data and thefacts as mentioned above are potential prospects in supporting opportunities cacao rind (shell) utilization ofwaste as a cattle feed. Shell cacao fruit has the potential to be processed as feed material reinforcing(concentrate). The quality of this waste can be improved through the process of fermentation. For ruminants(cattle and goats), cocoa shell waste after being processed, could be used as feed supports for accelerategrowth or increase milk productivity. Giving cocoa waste in cattle can improve the efficiency of reinforcinginputs, especially feed input from outside, namely in the form of waste bran cocoa fruit shell. The case study theopportunities cocoa shell waste utilization is done in the village Candikusuma, District Melaya, Jembrana whichis one of the village centers cocoa producer. Results of the study showed an area of 304.37 hectares of cocoaand cocoa production of 155.07 tones with certain assumptions derived rind (shell) dry cocoa as much as 57.38tons of dry cocoa shell, which potentially can be used as an alternative to feed rice bran reinforcing that costsmore expensive.
Keywords: Uilization, waste cocoa and cattle
ABSTRAK
Indonesia merupakan negara produsen kakao terbesar ke tiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghanadengan produktivitas dan kualitas yang masih rendah. Peningkatan produksi dan produktivitas kakao umumnyadiikuti oleh masalah, diantaranya penanganan limbah kakao dalam bentuk cangkang (kulit buah) kakao yangmencapai 73,77 % dari berat buah kakao segar. Limbah kakao belum banyak dimanfaatkan walaupun dalambeberapa kondisi memiliki potensi sebagai bahan pakan ternak maupun bahan baku pembuatan kompos.Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana memiliki luas perkebunan kakao rakyat tahun 2019 mencapai 1.384,40hektar dengan populasi ternak sapi mencapai 19.517 ekor. Data dan fakta tersebut di atas merupakan prospekpotensial dalam mendukung peluang pemanfaatan limbah kulit buah kakao sebagi pakan ternak sapi. Kulitbuah kakao memiliki potensi untuk diolah sebagai bahan pakan penguat (konsentrat). Mutu dari limbah inidapat ditingkatkan melalui proses fermentasi. Untuk ternak ruminansia (sapi dan kambing), limbah kulit kakaosetelah diolah, bisa dijadikan pakan penguat untuk mempercepat pertumbuhan atau meningkatkan produktivitassusu. Pemberian limbah kakao pada ternak sapi dapat meningkatkan efisiensi input terutama input pakanpenguat dari luar, yaitu berupa dedak dari limbah kulit buah kakao. Study kasus peluang pemanfaatan limbahkulit kakao dilakukan di Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Jembrana yang merupakan salah satu desasentra penghasil kakao. Hasil study memperlihatkan dengan luasan kebun kakao 304,37 hektar dan produksi
Peluang Pemanfaatan Limbah Kulit Buah Kakao Sebagai Pakan Termak SapiDi Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Jembrana | M.A. Widyaningsih
34 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara produsenkakao terbesar ke tiga di dunia setelah PantaiGading dan Ghana, dengan luas areal 1.740.612ha dan produksi 720.862 ton denganproduktivitas dan kualitas yang masih sangatrendah (Dirjen Perkebunan, 2014). Rata-rataproduktivitasnya hanya 821 kg/ha/tahun, masihjauh di bawah rata-rata potensi yang diharapkansebesar 1,54 -2,75 ton/ha/tahun, sedangkanPantai Gading produktivitasnya sudah mencapai1500 kg/ha/tahun (Anon, 2010). Beberapa faktoryang menyebabkan rendahnya produktivitas,adalah kondisi kebun yang kurang terawat,tanaman tidak produktif (tanaman sudah tua),serangan hama penyakit terutama serangan PBK(Penggerak Buah Kakao), Vascular StreakDieback (VSD), dan penyakit busuk buah(Phytopthora palmivora).
Desa Candi Kusuma, di Kecamatan Melaya,Jembrana Provinsi Bali, merupakan salah satudesa yang memiliki tanaman kakao. Datamenunjukkan, luas perkebunan kakao rakyat diKecamatan Melaya pada tahun 2017 adalah1.935,82 hektar, menurun menjadi 1.384,40hektar pada tahun 2014, demikian jugaproduksinya menurun dari 1.004,48 ton menjadi911,35 ton biji kakao kering (BPS, 2015). Daridata di atas terlihat produktivitas kakao diKecamatan Melaya meningkat dari 0,52 ton bijikakao kering per hektar pada tahun 2017 menjadi0,66 ton biji kakao kering/ha pada tahun 2014(BPS, 2015). Produktivitas kakao yang dihasilkandi tingkat petani ini jauh lebih rendah biladibandingkan dengan produktivitas kakao yangmencapai 0,70 s/d 0,90 ton biji kakao kering/hapada kegiatan Demplot Intensifikasi Kakao diSubak Abian Sumber Urip, Desa Pengragoan,Kecamatan Pekutatan dan di Subak Abian TamanSari, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya,Jembrana (Aribawa et al., 2011; Aribawa et al.,2012 dan Aribawa et al., 2013).
Peningkatan produksi dan produktivitaskakao umumnya diikuti oleh masalah,diantaranya penanganan limbah kakao dalambentuk cangkang (kulit buah) kakao yang
mencapai 73,77 % dari berat buah kakao segar(BPTP Bali, 2011). Penanganan limbahperkebunan sampai saat ini masih merupakankendala dalam program penanganan limbah ditingkat petani. Masalah ini di antaranya adalahketerbatasan waktu, tenaga kerja, maupunketerbatasan areal pembuangan. Di samping itu,limbah perkebunan belum banyak dimanfaatkanwalaupun dalam beberapa kondisi memilikipotensi sebagai bahan pakan ternak maupunbahan baku pembuatan kompos, sehingga perludilakukan pengamatan dalam mendukungprogram pemanfaatan limbah potensial.
Potensi limbah cangkang (kulit buah) kakaoyang belum banyak dimanfaatkan oleh petani,bisa dimanfaatkan untuk pakan alternatif untukternak sapi. Di beberapa lokasi seperti diKecamatan Melaya, Jembrana limbah kulit kakaosudah digunakan oleh beberapa peternak sapisebagai bahan pakan yang memberikankeuntungan bagi peternak sehingga perlu dikajilebih lanjut. Kecamatan Melaya, KabupatenJembrana memiliki luas perkebunan kakaorakyat tahun 2017 mencapai 1.384,40 hektardengan populasi ternak sapi mencapai 19.517ekor (BPS, 2015). Data dan fakta tersebut di atasmerupakan prospek potensial dalam mendukungpeluang pemanfaatan limbah kulit buah kakaosebagi pakan ternak sapi.
Pakan merupakan salah satu faktor yangsangat menentukan dalam usaha peternakan.Ketersediaan pakan sangat berfluktuasi,berlimpah pada musim hujan dan terjadikekurangan saat kemarau (Andayani, 2010). Haltersebut menjadi hambatan sekaligus tantanganbagi para peternak untuk tetap menyediakanpakan dengan kandungan protein yang tinggi,murah dan berkelanjutan. Nelson (2011)menyatakan bahwa penyediaan pakan telahbergeser kepada upaya eksplorasi danpemanfaatan bahan pakan nonkonvensionaldengan nilai kompetisi yang masih rendah antaralain adalah kulit buah kakao. Wulan (2001)menyatakan bahwa kulit buah kakao adalahlimbah utama hasil pengolahan buah kakao yangsangat potensial untuk dimanfaatkan.Mujnisa(2007) menyatakan bahwa pemanfaatan limbah
kakao 155,07 ton dengan asumsi tertentu diperoleh kulit buah kakao kering sebanyak 57,38 ton kulit kakaokering, yang berpeluang bisa dijadikan pakan penguat alternatif pengganti dedak padi yang harganya semakinmahal.
Kata kunci : Pemanfaatan, limbah kakao dan ternak sapi
35
hasil perkebunan atau limbah agroindustrimempunyai fungsi yaitu sebagai sumbermakanan berserat bagi ternak ruminansia.
Tulisan ini merupakan makalah review yangmembahas tentang peluang pemanfaatan limbahkulit buah kakao untuk pakan ternak sapi,khususnya peluang pemanfaatan limbah kulitbuah kakao di Desa Candikusuma, KecamatanMelaya, Jembrana, yang merupakan sentratanaman kakao
METODOLOGI
Bahan tulisan berasal dari data-datasekunder yang diperoleh dari kumpulan-kumpulan data-data informasi tentang peluangpemanfaatan limbah kulit buah kakao sebagaipakan ternak dan studi literatur memanfaatkanrefrensi dari buku-buku seperti Prosiding, Jurnal,Majalah Ilmiah Populer, Buletin dan lainnya.Refrensi juga diambil dari beberapa tulisan yangdimuat di media digital dan elektronik.Data selaludiikuti dengan penulisan sumber refrensi danapabila diperoleh secara elektronik selain sumberdata juga disertai dengan waktu pengunduhandata tersebut. Data disajikan dalam bentuk tabeldan grafik serta dianalisis secara deskritif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kakao dan Pemanfaatannya
Kecamatan Melaya dengan luas wilayahsekitar 197,19 km², merupakan satu dari limakecamatan yang terdapat di KabupatenJembrana, Bali. Berdasarkan ketinggian tanahdi bagian utara wilayah Kecamatan Melayamempunyai morfologi dan fisiografi dari landai,bergelombang sampai berbukit.Ketinggian tempat bervariasi antara 250 – 700m dpl. Sedangkan di bagian selatan wilayahKecamatan Melaya topografinya relatif datarhingga bergelombang, ketinggian tempat iniberkisar antara 1 – 250 m dpl. Kecamatan Melayamerupakan salah satu sentra penghasil buah/bijikakao di Kabupaten Jembrana (BPS, 2015).
Biji kakao, merupakan komoditi ekspor yangcukup menggembirakan karena mempunyai nilaiekonomis yang relatif tinggi di pasaran dunia,dibandingkan dengan produk dari tanaman
perkebunan lain. Pada tahun 2015, biji kakaoasalan di tingkat petani di Kecamatan Melayadibeli pengepul dengan harga Rp. 30.000,- s/d35.000,- per kg, harga ini bervariasi tergantungdari tingkat kekeringan dari biji kakao yang dijual.Harga biji kakao asalan maupun yangterfermentasi cenderung meningkat dan pasarlokal, regional, maupun internasional terutamapasar Eropa terbuka lebar dan masihmembutuhkan biji kakao.
Tanaman kakao, di samping menghasilkanproduk utama, berupa biji-bijian, minyak atauserat, juga menghasilkan produk sampinganberupa limbah. Limbah kakao, berupa kulit buahkakao memiliki potensi untuk diolah sebagaibahan pakan penguat (konsentrat) seperti lumpursawit, molasis, bungkil kelapa, buah semu mete,serta kulit buah kopi. Mutu dari limbah dapatditingkatkan melalui proses fermentasi, salahsatunya adalah dengan menggunakanAspergillus niger. Kulit buah kakao, setelahdifermentasi, dikeringkan kemudian ditepungkanagar bisa disimpan dalam jangka waktu yanglama (3-6 bulan). Proses fermentasi tersebutdapat meningkatkan kandungan protein kasar(CP) limbah kakao dari 9,23 % menjadi 17,42%.Selain itu juga dapat menurunkan kandunganserat kasarnya dari 16,42% menjadi 8,15%(Badan Litbang Pertanian, 2011).
Untuk ternak ruminansia (sapi dan kambing),limbah kulit kakao setelah diolah melaluifermentasi, bisa dijadikan pakan penguat untukmempercepat pertumbuhan atau meningkatkanproduktivitas susu. Pemberian limbah kakaopada ternak sapi dapat meningkatkan efisiensiinput terutama input pakan penguat dari luar,yaitu berupa dedak dari limbah kulit buah kakao.
Limbah Kulit Buah Kakao dan Pengolahannya
Limbah kakao, merupakan bahan yangterbuang di sektor perkebunan. Pada pertaniankonvensional atau modern, umumnya tidakterdapat pengelolaan limbah, sebab dalampertanian konvensional semua inputnya sepertipupuk menggunakan bahan kimia. Limbahdianggap suatu bahan yanag tidak penting dantidak bernilai ekonomi. Padahal jika dikaji dandikelola, limbah kakao ini dapat diolah menjadibeberapa produk baru yang bernilai ekonomitinggi.
Pengolahan limbah kakao sangat perludilakukan karena tanaman kakao merupakan
Peluang Pemanfaatan Limbah Kulit Buah Kakao Sebagai Pakan Termak SapiDi Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Jembrana | M.A. Widyaningsih
36 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
tanaman yang secara umum dimanfaatkanbagian bijinya saja. Bagian buah lain tidakdigunakan menjadi bahan utama dan umumnyadibuang dalam bentuk limbah. Limbah tanamankakao kebanyakan berupa limbah padat. Limbahpadat memiliki cara pengolahan yang berbeda.Secara umum, berdasarkan sifatnya,pengolahan limbah padat dapat dilakukan melaluidua cara yaitu diolah dan tanpa pengolahan.
Semakin meningkatnya produksi kakao baikkarena pertambahan luas areal pertanamanmaupun yang disebabkan oleh peningkatanproduksi persatuan luas, akan meningkatkanjumlah limbah buah kakao. Komponen limbahbuah kakao yang terbesar berasal dari kulitbuahnya atau biasa disebut pod kakao(cangkang kakao), yaitu sebesar 73,77 % daritotal buah (BPTP Bali, 2011)). Apabila limbah pod(kulit buah) kakao ini tidak ditangani secara seriusmaka akan menimbulkan masalah lingkungan.Di beberapa lokasi limbah kulit kakao sudahdigunakan oleh beberapa peternak sapi sebagaibahan pakan yang memberikan keuntungansehingga perlu dikaji lebih lanjut.
Pemanfaatan kulit buah kakao sebagaipakan ternak dapat diberikan dalam bentuk segarmaupun dalam bentuk tepung setelah diolah.Kulit buah kakao (shel food husk) adalahmerupakan limbah agroindustri yang dihasilkantanaman kakao (Theobroma cacao L.). Buahcoklat terdiri atas 74 % kulit buah, 2 % plasentadan 24 % biji. (Nasrullah dan Ella, 1993).MenurutGuntoro et al., (2006) Kulit buah kakao (Shel foodhusk) kandungan nutrisinya terdiri atas P 8,11%,SK 16,42%,L 2,11%,Ca 0,08%,P 0,12% danpenggunaannya oleh ternak ruminansia 30-40,sedangkan menurut Amirroenas (1990) kulitkakao mengandung selulosa 36,23%,hemiselulosa 1,14% dan lignin 20%-27,95%.Selanjutnya dikatakan bahwa limbah kulit buahkakao yang diberikan secara langsung kepadaternak justru akan menurunkan bobot badanternak, sebab kadar protein kulit buah kakaorendah, sedangkan kadar lignin dan selulosanyatinggi.
Mutu dari limbah dapat ditingkatkan melaluiproses fermentasi, salah satunya adalah denganmenggunakan Aspergillus niger. Fermentasidilakukan selama 5 hari, setelah itu bahankemudian dikeringkan kemudian ditepungkanagar bisa disimpan dalam jangka waktu yanglama (3-6 bulan). Melalui proses fermentasi, nilaigizi limbah kulit buah kakao dapat ditingkatkan,
sehingga layak untuk pakan penguat kambingmaupun sapi, bahkan untuk ransum babi danayam.
Potensi Perkembangan Perkebunan Kakaodan Ternak Sapi di Kecamatan Melaya,Jembrana
Kabupaten Jembrana, khususnya Keca-matan Melaya memiliki program pengembanganperkebunan kakao dan merupakan programpengembangan utama daerah, khususnyaperkebunan kakao rakyat. Perkembangan arealperkebunan kakao di Kecamatan Melayamenunjukkan perkembangan yang bervariasi(Tabel 1).
Tercatat pada tahun 2013 luas arealmencapai 1935,82 ha, tahun 2014 menyusutmenjadi 1384,40 hektar. Hal demikianberdampak terhadap total produksi kakao diKecamatan Melaya yakni pada tahun 2013produksi mencapai 1.004,48 ton, menurunmenjadi 911,35 ton di tahun 2017 (BPS, 2018).Kondisi demikian menggambarkan bahwa adapermasalahan di perkebunan kakao rakyat ditingkat petani. Menurunnya luas lahan kebunkakao di tingkat petani umumnya disebabkanoleh rendahnya produktivitas kakao yangdisebabkan oleh kondisi kebun yang kurangterawat, tanaman tidak produktif (tanaman sudahtua), serangan hama penyakit terutama seranganPBK (Penggerak Buah Kakao), Vascular StreakDieback (VSD), dan penyakit busuk buah(Phytopthora palmivora), disamping adanya alihfungsi lahan dari kebun kakao ke tanamantahunan lainnya.
Peluang Pemanfaatan Limbah Kulit BuahKakao Sebagai Pakan Ternak Sapi
Pemerintah dalam hal ini melalui dinasterkait secara simultan menyarankan untukmemanfaatkan produk sampingan pertanian/perkebunan sebagai sumber pakan alternatifbagi ternak yang dipelihara petani. Sumberpakan yang diberikan diharapkan mengandungzat makanan yang dibutuhkan oleh ternak,seperti serat dan protein, seperti yang terdapatpada limbah kulit buah kakao yang sudahterfermentasi. Untuk mengetahui peluang suatuarea atau subak abian dalam memenuhikebutuhan ternak akan pakan penguat alternatifseperti pemanfaatan kulit buah kakao ini, maka
37
diperlukan perhitungan dengan asumsi-asumsitertentu.
Seperti contoh untuk areal/wilayah DesaCandikusuma, Kecamatan Melaya di tahun 2017.Tindakan pertama adalah mengetahui luas areal(lahan) produksi tanaman kakao di DesaCandikusuma, selanjutnya mengetahuiproduktivitas buah kakao per hektare dan totalkeseluruhan produksi buah kakao di DesaCandikusuma. Setelah itu, menghitung produksilimbah kulit kakao berdasarkan total produksibuah kakao yakni 74 % dari buah kakao. Luasarael tanaman kakao di Desa Candikusuma:304,37 hektar Produksi buah kakao (ton/ha/th):0,51 ton Produksi buah kakao total (ton/ha/th) :155,07 ton/ha/tahun
Dari tinjauan pusataka di atas menunjukkanbahwa kulit buah kakao besarannya adalah 74% dari buah kakao, maka dengan demikianpeluang ketersediaan pakan pemguat alternatifdi Desa Candikusuma dari kulit buah kakaoadalah : 0,74 x 155,07 ton = 114,75 ton kulitbuah kakao basah. Dengan konversi bahwakakao kering mencapai 50 % dari produksi kulitbuah kakao basah, maka kulit buah kakao keringyang dihasilkan 0,50 x 114,75 ton = 57,38 ton.Jadi dengan demikian, untuk areal/lahan kebunkakao di Desa Candikusuma, Kecamatan Melayadengan asumsi tidak ada bahan kulit buah kakaoyang hilang dalam proses penepungan, makaakan dihasilkan 57,38 ton dedak kulit buah kakao
sebagai pakan penguat alternatif penggantidedak padi yang harganya semakin mahal, untukpakan ternak sapi sehingga dapat meningkatkanefisiensi input dalam beternak sapi.
KESIMPULAN
Dari hasil tinjauan pustaka yang dilakukan,maka dapat ditarik beberapa kesimpulandiantaranya adalah :luas lahan untuk kebunkakao rakyat di Desa Candikusuma paling luasbila dibandingkan dengan desa yang lainnya.Produktivitas kakao di Desa Candikusuma masihlebih rendah bila dibandingkan dengan potensihasil yang tercantum dalam deskiripsinya.Peluang dedak kakao sebagai pakan alternatifpenguat ternak sapi di Desa Candikusumaberpotensi mencapai 57,38 ton per tahun. Daripotensi di atas dapat dihitung kemampuan dayatampung ternak sapi untuk Desa Candikusuma,Kecamatan Melaya, Jembrana.
DAFTAR PUSTAKA
Andayani, J. 2010. Evaluasi kecernaan in vitrobahan kering, bahan organik dan proteinkasar penggunaan kulit buah jagungamoniasi dalam ransum ternak sapi. JurnalIlmiah Ilmu-Ilmu Peternakan Vol. XIII, No. 5.
Tabel 1. Luas perkebunan kakao rakyat, produksi dan produktivitas di Kecamatan Melaya, Jembrana
KakaoDesa Jumlah ternak sapi (ekor)
Luas (Ha) Produksi (Ton)
Gilimanuk - - 386Melaya 186,90 80,27 3.316Candikusuma 304,37 155,07 1.673Tuwed 196,60 156,53 1.691Tukadaya 152,13 152,15 3.330Manistutu 137,23 116,66 4.184Warnasari 31,81 17,32 1.421Nusasari199,81 92,34 1.077Ekasari 84,12 75,56 2.168Blimbingsari 91,43 65,45 271Jumlah 2017 1384,40 911,35 19.517
2016 1935,82 898,18 19.0642015 1936,49 518,41 18.9802014 1934,93 518,40 18.8182013 1935,82 1.004,48 10.702
Sumber : BPS (2018)
Peluang Pemanfaatan Limbah Kulit Buah Kakao Sebagai Pakan Termak SapiDi Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Jembrana | M.A. Widyaningsih
38 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
Aribawa, IB., IN. Sumawa, IBK. Swastika, IN.Duwijana dan I Made Sukarja. 2011. LaporanAkhir Demplot Gernas Kakao di Bali. BalaiPengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali,BBP2TP Bogor. Badan Litbang Pertanian.Jakarta.
Aribawa, IB., IN. Sumawa, IBK. Swastika, IN.Duwijana dan I Made Sukarja. 2012.Laporan Akhir Demplot Gernas Kakao diBali. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian(BPTP) Bali, BBP2TP Bogor. Badan LitbangPertanian. Jakarta.
Aribawa, IB., IN. Sumawa, IBK. Swastika, IN.Duwijana dan I Made Sukarja. 2013.Laporan Akhir Demplot Gernas Kakao diBali. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian(BPTP) Bali, BBP2TP Bogor. Badan LitbangPertanian. Jakarta.
Amirroenas D.E. 1990. Mutu ransum berbentukpellet dengan bahan serat biomasa podcoklat (Theobroma cacao L.) untukpertumbuhan sapi perah jantan.Tesis.(Tidakdipublikasikan). Fakultas Pascasarjana,Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Anonimus. 2010. Budidaya & Pasca PanenKakao. Puslitbangbun. Badan Litbangtan.Kementerian Pertanian. 92 hal.
Badan Litbang Pertanian. 2011. PengolahanLimbah Perkebunan untuk Pakan Ternak.Edisi 3-9 Agustus 2011 No.3417 Tahun XLIAgroinovasi, Badan Litbang Pertanian.
BPS. 2015. Kecamatan Melaya dalam Angka2014. Badan Pusat Statistk Denpasar. Bali
BPTP Bali. 2011. Pengolahan LimbahPerkebunan untuk Pakan Ternak. Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali,BBP2TP Bogor. Badan Litbang Pertanian.Jakarta. (un publish)
BPS. 2018. Kecamatan Melaya. Badan PusatStatistk Denpasar. Bali
Dirjen Perkebunan. 2014. Luas Areal, Produksidan Produktivitas Perkebunan di Indonesia.Kementerian Pertanian. Jakarta.
Guntoro, S., Sriyanto, N. Suyasa dan M. RaiYasa. 2006. Pengaruh pemberian limbahkakao olahan terhadap pertumbuhan sapiBali (Feeding of processed cacao by-productto growing bali cattle). Balai PengkajianTeknologi Pertanian Bali, Ngurah Rai,Denpasar.
Nasrullah dan A. Ella, 1993. Limbah pertaniandan prospeknya sebagai sumber pakanternak di Sulawesi Selatan. Makalah.(Tidakdipublikasikan).Ujung Pandang.
Nelson.2011. Degradasi bahan kering danproduksi asam lemak terbang in vitro padakulit buah kakao terfermentasi. Jurnal IlmiahIlmu-Ilmu Peternakan, Vol. XIV, No.1.
Mujnisa, A. 2007.Kecernaan bahan kering invitro, proporsi molar asam lemak terbangdan produksi gas pada kulit kakao, bijikapuk, kulit markisa dan biji markisa. BuletinNutrisi dan Makanan Ternak, Vol 6 (2).
Wulan, S. N. 2001. Kemungkinan pemanfaatanlimbah kulit buah kakao (Theobroma Cacao,L) sebagai sumber zat pewarna (Â-Karoten).Jurnal Teknologi Pertanian, Vol. 2,No. 2.
39
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI MELALUI TEKNOLOGIPERBENIHAN KOPI ROBUSTA KLON BP 308 DI LOKASI TTP
DESA SANDA KABUPATEN TABANAN
I Made Sukadana1, I Wayan Sunanjaya2, I Nengah Duwijana3
1,2,3)Penyuluh Balai Pengkajian Tekonologi Pertanian BaliJln. By Pass Ngurah Rai Pesanggran Denpasar,Tlp. (0361) 720498
E-mail: [email protected]
Submitted date : 16 Pebruari 2021 Approved date : 18 Maret 2021
ABSTRACT
Empowerment of Farmer Communities Through Robusta Clone BP 308 CoffeeSeeding Technology in TTP Location, Sanda Village, Tabanan Regency
Sanda Village is one of 14 villages in the Pupuan District area, located approximately 38 km to the northof the city center of Tabanan. Judging from the geographical conditions, the area of Sanda Village is a plateauwith an altitude of approximately 725 meters above sea level.The temperature ranges from 23-28 oC with anaverage rainfall of 1,050 mm/year.Togetherness and mutual cooperation are the capital to realize sustainabledevelopment efforts.The total population of Sanda Village in 2016 was 1,550 people with the community’slivelihoods being dominated by farming communities, namely 90%.As a farmer community actor who alsomanages agro educational tourism destinations “Agricultural Technology Plants (TTP)” requires mastery tomarket agro tourism objects entitled Integrated Robusta Coffee with Goat Cattle “.The problems faced in theeffort to cultivate the Robusta coffee plant and develop agro tourism include:First: Utilization of TechnologicalInnovations; Second: Community Empowerment: and Third: Problems with the development of a creativeeconomy community.To answer these problems, the concept of community empowerment in the form of Robustacoffee seed technology uses Robusta coffee cuttings Clone BP 308 as rootstock in interpreting the problem ofparasite nematodes.Physically, the technology that is being disseminated is in the form of BP 308 Robustacoffee propagation technology. The stages in the concept of community empowerment to the community are asfollows: (1) Identification of community needs, (2) Designing BP 308 Clone Technology.
Keywords: Empowerment, Sanda Village, technology, robusta coffee, BP 308 Clone entres cuttings
ABSTRAK
Desa Sanda merupakan salah satu dari 14 desa di wilayah Kecamatan Pupuan, terletak kurang lebih 38Km ke arah utata pusat kota Tabanan. Dilihat dari kondisi geografi, wilayah Desa Sanda merupakan datarantinggi dengan ketinggian kurang lebih 725 meter dari permukaan laut. Suhu udara berkisar antara 23-28 oCderngan curah hujan rata-rata 1.050 mm/tahun.Kebersamaan dan kegotongroyongan menjadi modal untukmewujudkan upaya pembangunan yang berkelanjutan. Jumlah penduduk Desa Sanda pada tahun 2016 adalah1.550 jiwa dengan mata pencaharian masyarakat didominasi oleh masyarakat petani yaitu 90%.Sebagai pelakumasyarakat petani yang juga mengelola tempat tujuan wisata edukasi agro “Tanaman Teknologi Pertanian(TTP)” memerlukan penguasaan untuk memasarkan obyek-obyek wisata agro yang bertajuk Kopi RobustaTerintegrasi dengan Ternak Kambing”. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya budidaya tanaman tanamankopi Robusta dan mengembangkan wisata agro antara diantaranya: Pertama : Pemanfaatan Inovasi Teknologi;Kedua : Perberdayaan Masyarakat: dan Ketiga : Permasalahan pengembangan masyarakat ekonomi kreatif.Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut maka konsep pemberdayaan masyarakat berupateknologi perbenihan kopi Robusta menggunakan stek entres kopi Robusta Klon BP 308 sebagai batang bawahdalam mengartasi masalah nematode parasite.Secara fisik teknologi yang didesiminasikan berupa teknologiperbanyakan kopi Robusta Klon BP 308. Tahapan dalam konsep pemberdayaan masyarakat kepada masyarakatsebagai berikut: (1) Identifikasi kebutuhan masyarakat, (2) Perancangan Teknologi Klon BP 308.
Kata kunci :Pemberdayaan, Desa Sanda, teknologi, kopi robusta, stek entres Klon BP 308
Pemberdayaan Masyarakat Petani Melalui Teknologi Perbenihan Kopi RobustaKlon BP 308 di Lokasi TTP Desa Sanda, Kabupaten Tabanan | I Made Sukadana, dkk.
40 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
PENDAHULUAN
Desa Sanda merupakan salah satu dari 14desa di wilayah Kecamatan Pupuan, terletakkurang lebih 38 Km ke arah utata pusat kotaTabanan. Desa Sanda memliki batas-batassebagai berikut : (1) Sebelah Utara : DesaBatungsel, (2) Sebelah Timur : Hutan Negara,(3) Sebelah Selatan : Desa Belimbing, danSebelah Barat : Desa Padangan dan Desa JelijihPunggang. Dilihat dari kondisi geografi, wilayahDesa Sanda merupakan dataran tinggi denganketinggian kurang lebih 725 meter daripermukaan laut. Suhu udara berkisar antara 23-28 oC derngan curah hujan rata-rata 1050 mm/tahun.
Salah satu ciri ciri masyarakat desa adalahpenduduknya masih memiliki hubungankekerabatan yang kental. Hubungan kekerabatanyang kuat ini cenderung dikarenakan antarkepala keluarga memiliki kemungkinan adanyahubungan keluarga. Karena hubungankekerabatan yang masih dinamis, kehidupanjuga memiliki ciri kekeluargaan dan juga memilikiikatan yang kuat meski tidak memiliki hubungandarah atau keluarga.
Ciri-ciri tersebut melekat pada masyarakatDesa Sanda memiliki semangat kerja yang baik.Komunitas petani Desa Sanda, memiliki adatbudaya dan sosial khususnya budaya gotongroyong. Kebersamaan dan kegotongroyongan inimenjadi modal untuk mewujudkan upayapembangunan yang berkelanjutan. Jumlahpenduduk Desa Sanda pada tahun 2016adalah1.550 jiwa dengan mata pencaharian masyarakatdi daerah ini didominasi oleh masyarakat petaniyaitu 90%.
Pemberdayaan masyarakat adalah prosespembangunan dimana masyarakat berinisiatifuntuk memulai proses kegiatan sosial untukmemperbaiki situasi dan kondisi yang ada.Pemberdayaan masyarakat pro aktif sertaberpartisipasi. Suatu usaha dapat berhasil dinilaisebagai “Pemberdayaan” apabila komunitas/masyarakat tersebut menjadi agen pemba-ngunan atau subjek (Subjek merupakan motorpenggerak dan bukan penerima manfaat atauobjek saja (Munanto, 2019). Lebih lanjutMardikanto (2014), ada 6 (enam) tujuan pember-dayaan masyarakat yaitu : 1) Perbaikankelembagaan, 2). Perbaikan usaha, 3). Perbai-kan pendapatan, 4). Perbaikan lingkungan, 5).Perbaikan kehidupan, 6). Perbaikan masyarakat.
Terbentuknya Tanaman Teknologi Pertanian(TTP), kedepan diharapkan dapat menunjangkegiatan masyarakat petani sebagai matapencaharian masyarakat Desa SandaKecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan yangsebagian besar bertani terutama pada padakomoditas perkebunan salah satunya tanamankopi Robusta disamping tanaman pertanian yanglainnya, dengan gagasan tersebut PemerintahanDesa bersama masyarakat berkeinginanmemberdayakan seluruh warga desa denganmembentuk Desa Agro Wisata yang di awalidengan pembentukan Taman TeknologiPertanian (TTP) bertajuk “Tanaman KopiTertintegrasi Dengan Ternak Kambing”.
METODOLOGI
Program pemberdayaan masyarakat inidilakukan selama 12 bulan mulaibulan Januarisampai Desember 2020. Sasaran kegiatan iniadalah masyakat petani kopi Robusta yangberlokasi di Tanamn Teknologi Pertanian (TTP)Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, KabupatenTabanan sejumlah 15 orang. Aspek yang dibahaspada kajian iniadalah implementasi teknologiperbenihan kopi klon BP 308 yang meliputipaktek pembuatan benih kopi Robusta denganmenggunakan bahan stek entres klon BP308.Metode pemberdayaan yang dilakukandengan menggunakan sosialisasi dan pelatihan,diskusi, praktik langsung, pendampingan danevaluasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Permasalahan Pemanfaatan Teknologi
Sebagai pelaku usaha wisata yangmengelola tempat tujuan wisata edukasi agroTanaman Teknologi Pertanian (TTP) memerlukanpenguasaan untuk memasarkan obyek-obyekwisata agro di Desa Sanda secara offline maupunonline. Selain itu Taman Teknologi Pertanian(TTP) dituntut juga untuk menyediakan teknologibaik dalam bidang pertanian, perkebunan danpeternakan disamping untuk memasarkan hasilpertanian yang dihasilkan oleh para petani diDesa Sanda meliputi: tanaman durian, apokat,pisang, termasuk buah lainnya dan bunga pecah
41
seribu yang mulai berkembang disekitar lokasiTaman Teknolog Pertanian (TTP), disamping ituuntuk pengembangan usahatani ternak kambingPE dan kambing Boerka yang sudah mulaiberkembang disekitar Desa Sanda denganmemanfaatkan inovasi teknologi.
Pemanfaatan inovasi teknologi untukpengembangan serta pemasaran hasil pertanian,perkebunan dan peternakan secara optimal.Pemasaran masih dilakukan secarakonvensional. Hal ini mengingat produktivitaskopi Robusta yang masih rendah untukdipasarkan. Teknologi perbenihan kopi Robustadiperlukan agar dapat meningkatkan hasilproduktivitas tanaman kopi yang selama iniproduksinya masih rendah.
Permasalahan pemberdayaan masyarakat
Taman Teknologi Pertanian (TTP) sebagaiujung tombak kegiatan wisata agro Desa Sadadalam hal ini kopi terintegrasi dengan ternakkambing masih mempunyai kendala dalambeberapa hal terkait pemberdayaan masyarakat,antara lain: (1) Penguatan tata kelola(manajemen) obyek-obyek wisata agro DesaSanda, (2) Peningkatan kemampuan untukmenggerakkan masyarakat sebagai pelakuusaha dalam kawasan wisata agro Desa Sanda.
Permasalahan pengembangan ekonomi kreatif
Pemberdayaan ekonomi masyarakat melaluipengembangan produk wisata agro melaluipenanaman terkonsentrasi pada masing-masingblok, antara lain : tanaman pertanian,
perkebunan, dan peternakan serta makananolahan. Peningkatan kegiatan produktifpenunjang destinasi wisata agro Desa Sanda.
Tahapan Pemberdayaan
Tahapan dan tindakan dalam melaksanakansolusi yang ditawarkan untuk mengatasipermasalahan, adalah sebagai berikut:
Metode dan tahapan dalam pemberdayaanmasyarakat
Kebutuhan masyarakat yang dimaksudkanantara lain sebagai berikut: (a) Kebutuhanterhadap sebuah kawasan pertanian kopiRobusta yang terpadu dengan fungsinya sebagaisalah satu obyek wisata agro di Desa Sanda; (b)Kebutuhan inovasi teknologi perbenihan kopirobusta yang efektif dan efisien berupa teknologibatang bawah kopi robusta yang menggunakanstek entres Klon BP 308.; (3) Kebutuhan inovasiteknologi pengembangan ternak kambingdisekitar Desa Sanda.
Perancangan teknologi Klon BP 308
Adapun perancangan yang dimaksudmeliputi: (a) Perancangan green house; (b)Perancangan inovasi teknologi stek entres KlonBP 308 (c) Perancangan kebun induk kopiRobusta Klon BP 308; (d) Perancanganlansekap; (e) Perancangan struktur organisasipengelola Taman Teknologi Pertanian (TTP)sebagai pusat taman untuk idukasi dibidangpertanian dan peternakan.
Gambar 1. Identifikasi Kebutuhan Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat Petani Melalui Teknologi Perbenihan Kopi RobustaKlon BP 308 di Lokasi TTP Desa Sanda, Kabupaten Tabanan | I Made Sukadana, dkk.
42 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
Untuk mempertahakan sifat tahan serangannematode kopi Robusta Klon BP 308 harusdiperbanyak secata klonal. Penggunaan sebagaibatang bawah dapat digunakan teknik stek-sambung dengan batang atas dari klon/varietasyang dikehendaki.
Teknologi perbanyakan kopi Klon BP 308
Kendala yang sering dihadapi petani dalambudidaya kopi salah satunya adalah nematodeparasit merupakan jasad pengganggu yangsangat berbahaya pada kopi Robusta maupunpada kopi Arabika. Sehingga merupakan salahsatu faktor penyebab terjadinya penurunanproduktivitas kopi ditentukan oleh serangannematoda parasit (Pratylenchus coffeae).Sampaisaat ini belum ada cara pengendalian yangbersifat ekonomis untuk pertanaman kopi yangsudah terserang. Dipihak lain nematode parasittersebut telah dijumpai diseluruh sentrapenghasil kopi di Indonesia, oleh karena itudiperlukan upaya sungguh-sungguh untukmengatasinya. Dari aspek praktis dan ekonomis,penggunaan bahan tanaman unggul tahannematode masih merupakan cara pengendalianyang paling efektif dan efisien.
BPTP Balitbangtan Bali pada tahun 2020telah berhasil memproduksi benih kopi Robustasebanyak kurang lebih 21,000 pohon yang telah
tersertifikasi. Klon BP 308 dilepas oleh MenteriPertanian dengan SK No. 65/Kpts/SR.120/I/2004. Klon kopi BP 308 merupakan klon kopirobusta yang direkomendasikan sebagai batangbawah, hal ini dapat terbukti tahan terhadapserangan nematode parasit. Disamping itu,KlonBP 308 mempunyai keunggulan tahan terhadapserangan hama nematode parasit. Strukturbatang dan akar sangat kuat, toleran terhadapkondisi tanah tidak subur, mempunyai produksiyang cukup baik sekitar 1,200 ton/ha dan toleranterhadap cekaman kekeringan.Teknispelaksanaan teknologi perbanyakan kopiRobusta Klon BP 308 sebagai batang bawangadalah sebagai beriku :
Bahan dan Alat
• Perbanyakan benih kopi Robustamenggunakan batang bawah Klon BP 308dapat dilakukan memilih stek/ros denganukuran panjang 5-7 cm.
• Bahan lain yang disiapkan berupa mediatanam tanah, kompos/pupuk kandang dancocopit (2:1:1), polybag ukuran 14 x 23 cm,ZPT akar, Beka Decomposer Plus, plastiksungkup.Sedangkan bahan yang digunakanuntuk pembuatan rumah bibit diantaranyaparanet, bambu dan tali rapia.
• Peralatan yang digunakan cangkul, skop,
Deskripsi Diseminasi Inovasi Teknologi
Deskripsi singkat kopi robusta klon BP 308
Sifat agronomi Deskripsi
Perakaran Besar, kokohPercabangan Cabang primer teratur agak mendatar, reproduksi cabang cukup aktif,
cabang sekender agak terpuntirDaun Berwana hijau tua gelap, pupus merah kecoklatan,helaian daun membusur,
permukaan daun bergelombang dan menyudut, tepi daun bergelombangtegas
Perakaran Melebar akar leteral banyakPembungaan Agak lambat menjelang akhir musim pembungaanBuah Kecil tidak seragam, diskus kecil, buah muda beralur tegas, buah masak
merah hatiBiji Kecil, presentase biji tunggal tinggi (62%)Produktivitas 1.200 Kg kopi pasar/ha/tahunCatatan :Keunggulan Klon BP 308 Selain tahan serangan nematode parasit, juga tahan kekeringanKelemahan BP Klon 308 Sebagai induk maupun penyerbuk mewariskan sifat tahan hanya sebesar
40-60%, sehingga harus diperbanyak secara klonial
Sumber : PuslitKoka, 2008.
43
Gambar 2. Proses teknologi perbenihan kopi Robusta Klon BP 308 sebagai batang bawah
Penyediaan stek entres kopi Robusta Klon BP 308 Pemotongan stek entres kopi Robusta Klon BP 308
Perendaman stek entres kopi Robusta Klon BP 308 Penyiapan campuran media tanamdengan zat pengatur akar
Penanaman stek entres Kopi Robusta Klon BP 308 Penyungkupan stek entres kopi Robusta Klon BP 308
Sertifikasi benih kopi Robusta Klon BP 308 Benih kopi Robusta Klon BP 308 batang bawah siapbatang bawah diserahkan ke masyarakat petani
Pemberdayaan Masyarakat Petani Melalui Teknologi Perbenihan Kopi RobustaKlon BP 308 di Lokasi TTP Desa Sanda, Kabupaten Tabanan | I Made Sukadana, dkk.
44 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
alat angkut/arco, sabit, gergaji, golok, linggis,meteran, benang sepat, gunting pangkasdan pisau okulasi.
Rumah Bibit
• Rumah bibit dapat dibuat denganmenggunakan menggunakan tiangbambudan atap paranet dengan penyinaranantara 40-60%, tiang bambu setinggi ± 200cm dengan panjang dan lebar dapatdisesuaikan dengan tempat/lokasi danjumlah benih kopi yang akan dibutuhkan.
• Selanjutnya dibuat tempat polybag benihkopi dengan lebar 120 cm dengan panjangdisesuaikan dengan tempat benih kopi.
Penyiapan Media Tanam
• Siapkan media tanam untuk menumbuhkanakar dari batang yang distek.
• Media tanam ini harus memiliki drainaseyang baik dan bisa mencengkram batangdengan kokoh.
• Campuran media tanam berupa tanahsubur,cocopit dan kompos/pupuk kandangdengan perbandingan 2:1:1.
• Peremdaman stek/ros dengan larutan ZPTakar.
Pelaksanaan Perbenihan Kopi Robusta KlonBP 308
Rincian pelaksanaan kegiatan pembuatanbenih kopi Robusta Klon BP 308 dapatdilaksanakan diantaranya :• Penyediaan batang bawah melalui
pemotongan stek/ros klon BP 308. Bahanyang digunakan untuk stek hendaknyadiambil tunas-tunas air (wiwilan) yangberasal dari kebun induk entres. Stek yangberasal dari wiwilan kebun produksibiasanya kurang baik. Ruas yang baikadalah ruas no. 2 dan 3, makin tua umurbahan stek, makin kecil daya perakarannya.Stek terdiri dari 1 (satu) ruas dipotongruncing sepanjang 5- 7 cm dengansepasang daun yang dikupir hingga + 4 cm.Bagian pangkal dipotong miring satu arah.
• Peremdaman stek entres denganmenggunakan larutan ZPT akar selamakurang lebih 15 menit.
• Meniriskan stek entres yang telah direndamdengan larutan Growntone.
• Penanaman stek kedalam polybag yangtelah disiapkan.
• Penyemprotan stek/ros denganmenggunakan larutan Beka DecomposerPlus dengan perbandingan air sebanyak 2cc : 1 liter.
• Penyungkupan tanaman stek entres denganmenggunakan plastik sungkup dilakukansetelah semua stek ditanam.
KESIMPULAN DAN SARAN
Peran serta kepemimpinan baik formalmaupun non formal sangat diperlukan untukmeningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Jugaperlu digali potensi sosial budayayang telahdimiliki oleh masyarakat desa. Upaya tersebutantara lain dengan memanfaatkan lembagayang ada seperti masyarakat petani sadar wisatayang merupakan wadah masyarakat dalammenyampaikan aspirasinya dan lebihmenghidupkan lagi suasana kebersamaan dangotong-royong yang kental mewarnai kehidupandesa.
Dengan dukungan 504 kepala keluargayang berprofesi sebagai masyarakat petanitanaman kopi Robusta dan tanaman lainnyadiharapkan berpartisipasi aktif untukmensukseskan Wisata Agro yang berlokasi diTaman Teknologi Pertanian (TTP) Desa Sandabertajuk Tanaman Kopi terintegrasi denganternak kambing dapat terwujud danberkelanjutan.
DAFTAR PUSTAKA
Anwas, Oos M. (2013). PemberdayaanMasyarakat Di Era Global. Bandung:Alfabeta
Chambers, Robert. (1996). PRA ParticipatoryRural Appraisal Memahami Desa SecaraPartisipatif. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ProvinsiBali, tahun 2019. Program PenyuluhanProvinsi Bali Tahun 2020, Dinas Pertaniandan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun2019.
45
Mardikanto, Totok. (2014). CSR (CorporateSocial Responsibility) (TanggungjawabSosial Korporasi). Alfabeta. Bandung.
Munanto, H., 2019. Pemberdayaan MasyarakatPetani Dusun Grangsel, Jambangan MelaluiTeknologi Hidroganik dan Energi MandiFotovoltaik. Jurnal PenyuluhanPembangunan Volume 1, Nomor 2 Tahun2019.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 49/Permentan/OT.140/2014. Pedoman TeknisBudidaya Kopi Yang Baik (Good AgriculturePractices/GAAP On Caffee). DirektoratJndral Perkebunan. KementerianPertanian.Peraturan Menteri PertanianRepublik Indonesia Nomor: 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produyksi,Sertifikasi, Peredaran dan PengawasanBenih Tanaman Perkebunan.
Puslit Koka, 2014. Kopi Tahan Nematoda KlonBP 308 dan Perbanyakannya. Leaflet. No,0519/HK.1301.42/02/08, tanggal 20Pebruari 2008.
Sunanjaya, I.W., Yasa, I.R., Adijaya, I.N., Rdsiani,D.M.Ni., Sukadana. I.M., Dwijana. I.N.,Sukraeni, K.K.Ni., Elizabeth, S.P.,Adiwirawan, P.L.Ngr.Gst., Suana, I.N.Kudiana, I.M., Suardama. I.K. 2020.Produksi Benih Sebar Kopi Robusta.Laporan Akhir Tahun. Balai PengkajianTeknologi Pertanian Bali. Balai BesarPengkajian dan Pengembangan TeknologiPertanian. Badan Penelitian danPengembangan Pertanian. KementerianPertanian. 2020
Pemberdayaan Masyarakat Petani Melalui Teknologi Perbenihan Kopi RobustaKlon BP 308 di Lokasi TTP Desa Sanda, Kabupaten Tabanan | I Made Sukadana, dkk.
46 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
PERILAKU PESERTA TEMU TEKNIS INOVASI PERTANIANTENTANG PENGOLAHAN BAWANG MERAH
I Wayan Alit Artha Wiguna1, I Gusti Made Widianta2,Ni Ketut Sudarmini3, Agung Prijanto4
1,2,3,4)Penyuluh Pertanian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BaliJln. By Pass Ngurah Rai Pesanggran Denpasar,Tlp. (0361) 720498
E-mail : [email protected]
Submitted date : 22 Januari 2021 Approved date : 26 Pebruari 2021
ABSTRACT
Behavior of Participants of Agricultural Innovation Technical Meetingabout Shallot Processing
The Behavior of Participants in the Agricultural Innovation Technical Meeting about Shallot Processing isthe result of an evaluation for the participants on agricultural innovation meeting, was done on 2019 and 2020.Meeting was carried out by the Assessment Institute for Agricultural Technology (AIAT) of Bali. The activitieswas done in three regencies (Buleleng, Tabanan and Bangli) and as well as an innovation meeting at theprovincial level of Bali. To determine the changes of participants’ behavior regarding shallot processing technology.Data were collected, through pre and post tests, and analyzed by descriptive methode. Total number ofrespondents is 131 participants, with ages range between 23 and 60 years. Participants who have the status ofagricultural extension agents have an age range between 23 and 60 years old, with an average of 48.93 years.Furthermore, participants with non-extension status had an age range between 26 and 57 years old with anaverage of 44.29 years. Meanwhile, participants who work as farmers have an age range between 23 and 53years old, with an average of 40.46 years. About 76.3% of the participants in the innovation meeting wereagricultural extension workers; 5.3% non-extension workers; 18.3% are farmers. The innovation meeting led toa change in the level of participants’ knowledge shallot processing technology after participating in the innovationmeeting. The results of these analysis illustrate that the agricultural innovation meeting on shallot processingcarried out by the AIAT for 2019-2020, has an important role in increasing participants’ knowledge. In addition,the results of the evaluation also showed that the participants’ attitudes about shallot processing technologychanged to a more positive direction after the participants took part in the 2019-2020 innovation meeting. Thusthe agricultural innovation meetings held by AIAT of Bali in 2019 and 2020 regarding shallot processing, wereable to increase participants’ knowledge and attitudes towards a better direction. The finding of agriculturalinnovation has a great opportunity to accelerate the process of adoption of innovative agricultural technologyinnovations from Agriculture Research Centre. Therefore, it is better if AIAT continue to find innovations forvarious agricultural technologies produced by Agriculture Research Centre. Because there will be an opportunityto accelerate the process of agricultural adoption-innovation from Agriculture Research Centre to farmers astechnology users. Furthermore, in determining the innovation meeting participants as far as possible areparticipants with higher education and profesional job levels and who are still productive in age catagories.
Keyword: Behavior, technical innovation meeting, shallot processing.
ABSTRAK
Perilaku Peserta Temu Teknis Inovasi Pertanian tentang Pengolahan Bawang Merah merupakan hasilevaluasi yang dilakukan terhadap peserta temu inovasi pertanian tahun 2019 dan 2020, yang dilaksanakanoleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali, di tiga kabupaten (Buleleng, Tabanan dan Bangli) serta temuinovasi tingkat provinsi Bali. Untuk mengetahui perubahan perilaku peserta tentang teknologi pengolahan bawangmerah, maka dilakukan pengumpulan data melalui pre dan post test, yang selanjutnya dianalisis secaradescriptive. Hasil analisis data menunjukann bahwa jumlah peserta temu inovasi tahun 2019-2020 tentang
47
pengolahan bawang merah adalah sebanyak 131 orang, dengan umur berkisar antara 23 dan 60 tahun. Pesertayang berstatus sebagai penyuluh pertanian memiliki rentang umur antara 23 dan 60 tahun dengan rataan48,93 tahun. Selanjutnya peserta yang berstatus non-penyuluh memiliki rentangan umur antara 26 dan 57tahun dengan rataan 44,29 tahun. Sedangkan peserta yang berprofesi sebagai petani memiliki rentanganumur antara 23 dan 53 tahun dengan rataan 40,46 tahun. Peserta temu inovasi sebanyak 76,3% adalah penyuluhpertanian; 5,3% non penyuluh; 18,3% adalah petani. Temu inovasi menyebabkan adanya perubahan tingkatpengetahuan peserta tentang teknologi pengolahan bawang merah setelah mengikuti temu inovasi. Hasil analistersebut menggambarkan bahwa temu inovasi pertanian tentang pengolahan bawang merah yang dilakukanoleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali tahun 2019-2020, memiliki peran penting dalam meningkatkanpengetahuan peserta. Selain itu hasil evaluasi juga menunjukan bahwa sikap peserta tentang teknologipengolahan bawang merah berubah ke-arah yang lebih positive setelah peserta mengikuti temu inovasi tahun2019-2020. Dengan demikian temu inovasi pertanian yang diselenggarakan BPTP Bali tahun 2019 dan 2020tentang pengolahan bawang merah, mampu meningkatkan pengetahuan dan sikap peserta ke-arah yang lebihbaik. Temu inovasi pertanian sangat berpeluang untuk mempercepat proses-adopsi inovasi teknologi pertanianinnovative hasil Balitbangtan. Oleh karena itu sebaiknya temu inovasi untuk berbagai teknologi pertanian yangdihasilkan Balitbangtan dapat terus dilakukan. Karena akan berpeluang untuk mempercepat proses adopsi-inovasi pertanian dari Balitbangtan kepada petani sebagai pengguna teknologi. Selanjutnya dalam menentukanpeserta temu inovasi sedapat mungkin adalah peserta dengan Pendidikan dan jenjang fungsional yang lebihtinggi dan usia yang masih produktif.
Kata kunci: Perilaku, temu inovasi pertanian, pengolahan bawang merah.
inovasi pertanian, baik di tingkat provinsi maupunkabupaten. Tulisan ini akan membahas tentanghasil evaluasi terhadap perubahan prilakupeserta temu inovasi pertanian tentang teknologipengolahan bawang merah, yang merupakansalah satu materi yang dibahas dalam temuinovasi tersebut.
METODOLOGI
Waktu dan Tempat
Evaluasi dilaksanakan pada saatpenyelenggaraan temu inovasi pertanian olehBalai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali padatahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019,dilakukan di empat lokasi yaitu: KabupatenBangli, Buleleng dan Tabanan dan di tingkatProvinsi. Untuk kabupaten Bangli dilakukan diBalai Penyuluhan Pertanian (BPP) Bangli padatanggal 19 Agustus 2019 Untuk kabupatenBuleleng dilaksanakan di BPP Sukasada padatanggal 8 Mei 2019 dan kabupaten Tabanandilaksanakan di BPP Penebel pada tanggal 14Juni 2019 Sedangkan untuk tingkat provinsidilaksanakan di BPP Abiansemal pada tanggal15 April 2019. Selanjutnya untuk tahun 2020,dilaksanakan di Kelompok Wanita Tani MudiSejahtera, Desa Batur Selatan, kecamatanKintamani pada tanggal 12 Maret 2020.
PENDAHULUAN
Hingga tahun 2017, Balibangtan telahmenghasilkan lebih dari 600 teknologi pertanianinovatif, salah satu di antaranya adalah teknologipengolahan bawang merah. Namun sebagianbesar teknologi tersebut belum dimanfaatkanoleh pengguna, terutama petani sebagai pelakuutama. Kurang atau tidak diketahuinya teknologitersebut merupakan salah satu alasannya.Kurangnya pengetahuan, sikap dan keterampilanpelaku utama tentang sebuah teknologiinnovative, dapat diatasi melalui penyuluhan olehpenyuluh pertanian. Oleh kerena itu penyuluhpertanianpun harus memiliki pengetahuan yangmumpuni tentang teknologi yang akandisuluhkan. Salah satu upaya yang dapatdilakukan untuk meningkatkan pengetahuan,sikap dan keterampilan seseorang adalahmelalui sebuah diseminasi, dalam berbagaibentuk, salah satunya adalah temu teknis inovasipertanian. Temu teknis inovasi pertanian adalahsebuah pertemuan antara peneliti, penyuluh danpetani untuk membahas suatu teknologi yangdibutuhkan petani sebagai pengguna teknologi.Tujuannya adalah untuk meningkatkanpengetahuan, sikap, keterampilan pesertatentang sebuah teknologi yang dibahas ataudidiskusikan. Pengetahuan, sikap danketerampilan seseorang merupakan factor-faktoryang berperan dalam perilaku seseorang. BalaiPengkajian Teknologi Pertanian Bali, sejak tahun2019 telah melakukan kegiatan temu teknis
Perilaku Peserta Temu Teknis Inovasi Pertanian Tentang PengolahanBawang Merah | I Wayan Alit Artha Wiguna, dkk.
48 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
Proses Koleksi Data
Data dikumpulkan atau dikoleksi denganmenggunakan daftar pertanyaan tertutupterhadap peserta. Seluruh pertanyaan berkaitandengan karakteristik peserta dan pengetahuanserta sikap peserta. Terdapat dua jenis data yangdikoleksi, yaitu data sebelum pelaksanaan temuinovasi pertanian yang disebut dengan pre testdan data dengan pertanyaan yang samadikoleksi setelah pelaksanaan temu inovasi yangdisebut dengan post test. Bedasarkan keduajenis data tersebut (pre dan post test) akandiketahui perubahan pengetahuan dan sikappeserta tentang teknologi pengolahan bawangmerah yang didiskusikan antara peneliti sebagainara sumber; penyuluh dan petani sebagaipeserta.
Analisis Data
Analisis data dilakukan secara descriptiftehadap perubahan pengetahuan dan sikappeserta tentang teknologi pengolahan bawangmerah. Untuk pengetahuan peserta dibedakanmenjadi lima katagori yaitu: 1) Sangat rendahdengan skor 0-20; 2) Rendah (>20-40); 3)Sedang (>40-60); 4) Tinggi (>60-80) dan 5)Sangat Tinggi (>80-100). Skor pengetahuanpeserta bersumber dari 10 pertanyaan yangdiajukan melalui daftar pertanyaan yang telahdisiapkan. Nilai masing-masing pertanyaanpaling tinggi adalah 100 dan paling rendah adalah0. Pemberian skor tersebut didasarkan padaskala Likert.
Sedangkan sikap juga dibedakan menjadilima katagori, yaitu: 1) Sangat Tidak Setujudengan skor 1; 2) Tidak Setuju dengan skor 2;3) Biasa saja dengan skor 3; 4) Setuju denganskor 4 dan 5) Sangat Setuju dengan skor 5. Nilai1 sampai dengan 5 berasal dari 10 pertanyaanyang berkaitan dengan sikap seseorangterhadap teknologi pengolahan bawang merah.Nilai atau skor setiap pertanyaan paling rendahadalah 1 dan paling tinggi adalah 5. Semakinpositive sikap seseorang maka skornya semakintinggi, demikian sebaliknya semakin negativesikap seseorang maka nilai atau skornyasemakin rendah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Peserta Temu Inovasi
Umur Peserta Temu Inovasi
Jumlah peserta temu inovasi tahun 2019-2020 tentang pengolahan bawang merah adalahsebanyak 131 orang, dengan rentagan umurberkisar antara 23 dan 60 tahun. Peserta yangberstatus sebagai penyuluh pertanian memilikirentang umur antara 23 dan 60 tahun denganrataan 48,93 tahun. Selanjutnya peserta yangberstatus non-penyuluh memiliki rentangan umurantara 26 dan 57 tahun dengan rataan 44,29tahun. Sedangkan peserta yang berprofesisebagai petani memiliki rentangan umur antara23 dan 53 tahun dengan rataan 40,46 tahun.Dilihat dari segi umur, maka seluruh pesertamerupakan peserta dengan usia productive,bahkan jika dilihat dari rataan umur peserta,maka dapat dikatakan bahwa sebagian pesertamerupakan masyarakat yang ada pada usia yangsangat produktive. Sejalan dengan Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, yangmenyatakan bahwa usia kerja productive adalahmereka yang berusia antara 15 dan 64 tahun.Selanjutnya BPS (2017) membedakan usiaproductive menjadi dua katagori, yaitu: 1) Usiasangat productive antara 15 dan 49 tahun; dan2) Usia Produktive antara 50 dan 64 tahun.
Lebih jauh BPS (2017) juga menyebutkanbahwa di Indonesia pada tahun 2016, jumlahperempuan usia sangat produktif mencapai 69,4juta, lebih sedkit dibanding laki-laki yangmencapai 70,4 juta jiwa. Sedangkan untuk usiaproduktif (50-64), perempuan lebih banyakdengan 16,91 juta, sedangkan laki-laki hanya16,9 juta jiwa. BPS (2017) juga menyatakanbahwa kondisi tersebut menunjukkan bahwaIndonesia tengah memasuki era bonusdemografi, dimana kelebihan penduduk usiaproduktif bisa dimanfaatkan untuk peningkatanpembangunan. Diperkirakan, era bonusdemografi tersebut akan mencapai puncaknyapada periode 2025–2030. Di lain pihak Lubis(2000) menyatakan bahwa semakin muda umurpetani, maka akan semakin semangat untuk
49
mengetahui hal baru. Sehingga merekaberusaha untuk lebih cepat melakukan adopsiinovasi. Pernyataan tersebut menunjukan bahwasemakin muda umur petani, maka peluang terjadiadopsi-inovasi sebuah teknologi pertanian akansemakin cepat.
Status Peserta Temu Inovasi
Jumlah responden dalam kegiatan temuteknis inovasi pertanian yang diselenggarakanoleh BPTP Bali tahun 2019 dan 2020, adalahsebanyak 131 orang (Tabel 1 dan Gambar 1).Tabel 1 juga menunjukan bahwa dari 131 orangpeserta temu teknis inovasi tahun 2019 dan2020, sebanyak 76,3% adalah penyuluh
pertanian; 5,3% non penyuluh; 18,3% adalahpetani. Selain itu Tabel 1 juga menunjukan bahwapeserta temu inovasi dilaksanakan di empatlokasi yaitu di kabupaten Tabanan, Buleleng,Bangli dan di provinsi Bali. Hasil analisis dataterhadap karakteristik peserta temu inovasi,menggambarkan bahwa peserta temu inovasiadalah para penyuluh pertanian, petani danpengambil kebijakan dengan narasumber adalahpeneliti. Sejalan dengan batasan tentang temuinovasi, yang merupakan pertemuan antarapeneliti, penyuluh dan petani. Dalam hal inipeneliti adalah sebagai narasumber, sedangkanpenyuluh adalah perantara antara penelitisebagai penghasil teknologi dengan petanisebagai pengguna teknologi yang juga didukung
Tabel 1. Karakteristik peserta temu teknis inovasi pertanian tahun 2019 - 2020 di Bali tentang teknologipengolahan bawang merah
Gambar 1. Karakteristik peserta temu teknis inovasi pertanian tahun 2019 - 2020 di Bali tentang teknologipengolahan bawang merah
Perilaku Peserta Temu Teknis Inovasi Pertanian Tentang PengolahanBawang Merah | I Wayan Alit Artha Wiguna, dkk.
50 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
oleh pengambil kebijakan. Ke-empat stakeholdertersebut memiliki peran penting dalam sebuahproses penyelenggaraan penyuluhan.
Petani sebagai pelaku usaha, sangatmembutuhkan sebuah tekologi innovative yangdihasilkan oleh peneliti. Di lain pihak parapenyuluh yang memiliki tugas pokok dalammentransfer teknologi, harus sejalan dengankebijakan-kebijakan yang dikeluarkan olehpengambil kebijakan yang umumnya merekabukalah seorang penyuluh pertanian, namun
mereka adalah birokrasi. Oleh karena it uke-empat komponen tersebut harus mampubekerjasama dalam sebuah prosespenyelenggaraan penyuluhan yang tujuanadalah merubah perilaku petanu sebagaisasaran dan pelaku utama teknologi innovative.
Pendidikan Peserta Temu Inovasi
Selanjutnya Tabel 2 dan Gambar 2menunjukan bahwa sebagian besar peserta
Tabel 2. Tingkat pendidikan peserta temu inovasi tahun 2019-2020 di Bali tentang teknologi pengolahan bawangmerah
Gambar 2. Tingkat pendidikan peserta temu inovasi pertanian tahun 2019-2020 di Bali tentang teknologipengolahan bawang merah
51
Tabel 3. Katagori pengetahuan peserta temu inovasi pertanian tahun 2019-2020 di Bali tentang teknologipengolahan bawang merah
memiliki Pendidikan Perguruan Tinggi (PT) yangmencapai 65,6%; disusul oleh Pendidikan SLTAsebanyak 16,8%; SD sebanyak 12,2% dan SLTPsebanyak 5,3%. Peserta yang berpendidikan SDpaling banyak berasal dari kabupaten Bangliyang mencapai 66,7% dari 49 orang peserta.
Sedangkan peserta yang berprofesi sebagaipenyuluh pertanian sebanyak 81 orang sebagianbesar berpendidikan PT yang mencapai 81,0%dan hanya 19,0% yang berpendidikan SLTA.Demikian pula halnya dengan peserta yang nonpenyuluh pertanian, sebanyak 71,4%berpendidikan PT dan hanya 28,6% yangberpendidikan SLTA. Relative cukup tingginyaPendidikan peserta temu inovasi, diharapkanakan memperkuat tingkat adopsi teknologi yangakan disuluhkan oleh penyuluh pertanian, karenaPendidikan memiliki peran penting dalam sebuahproses adopsi-inovasi. Sejalan dengan Lubis(2000) yang menyatakan bahwa pendidikanmerupakan sarana belajar dimana selanjutnyaakan menanamkan sikap pengertian yangmenguntungkan menuju pembangunan praktekpertanian yang lebih modern. Mereka yangberpendidikan tinggi adalah yang relatif lebihcepat dalam melaksanakan adopsi, begitu pulasebaliknya mereka yang berpendidikan rendah,agak sulit melaksanakan adopsi inovasi dengancepat.
Pengetahuan Peserta Temu Inovasi tentangTeknologi Pengolahan Bawang Merah
Pengetahuan peserta temu inovasi tahun2019-2020 di Bali tentang teknologi pengolahanbawang merah pada saat pre test untuk yangberstatus penyuluh pertanian sebagian besar(36,0%) ada pada katagori tinggi (Tabel 3 dan
Gambar 3). Kemudian disusul oleh pengetahuandengan katagori sedang (35,0%); rendah(21,0%); sangat rendah (5,0%) dan sangat tinggi(3,0%). Pengetahuan peserta dengan statuspenyuluh pertanian berubah menjadi sangattinggi (32,0%); tinggi (52,0%); sedang (15,0%);rendah (1,0%) dan sangat rendah (0,0%).
Sedikit berbeda dengan peserta yangberstatus sebagai Non-Penyuluh, pada saat pretest, memiliki tingkat pengetahuan dengankatagori sangat rendah (0,0%); rendah (28,6%);sedang (14,3%); tinggi (57,1%) dan sangat tinggi(0,0%). Tingkat pengetahuan tersebut pada saatpost test mengalami perubahan menjadi sangatrendah dan rendah masing-masing 0,0%; sedang14,3%; tinggi (57,1%) dan sangat tinggi (28,6%).Perubahan pengetahuan setelah mengikuti temuinovasi juga terjadi pada peserta dengan statussebagai petani. Pada saat pre test tingkatpengetahuan petani tentang teknologipengolahan bawang merah adalah sangatrendah (8,3%); rendah (29,2%); sedang (41,7%);tinggi (20,8%) dan sangat tinggi (0,0%).Pengetahuan tersebut berubah menjadi sangatrendah (0,0%); rendah (4,2%); sedang (29,2%);tinggi (66,7%) dan sangat tinggi (0,0%).
Perubahan tingkat pengetahuan pesertatentang teknologi pengolahan bawang merahsetelah mengikuti temu inovasi menggambarkanbahwa temu inovasi pertanian tentangpengolahan bawang merah yang dilakukan olehBalai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali tahun2019-2020, memiliki peran penting dalammeningkatkan pengetahuan peserta. Sepertidiketahui bahwa pengetahuan seseorangtentang sebuah inovasi merupakan salah satufactor penting dalam proses adopsi teknologi.Sejalan dengan Rogers (2003) dalam Putri
Perilaku Peserta Temu Teknis Inovasi Pertanian Tentang PengolahanBawang Merah | I Wayan Alit Artha Wiguna, dkk.
52 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
(2011), yang menyatakan bahwa beberapatahapan adopsi dari proses pengambilankeputusan inovasi mencakup: 1) TahapPengetahuan (Knowledge) yaitu ketika seorangindividu mulai mengenal adanya inovasi danmemperoleh berbagai pengertian tentangbagaimana fungsi/ kegunaan dari inovasitersebut.
Sebelumnya Mardikanto (1996) menyatakanbahwa adopsi dalam proses penyuluhan padahakekatnya dapat diartikan sebagai prosesperubahan perilaku lain yang berupapengetahuan (cognitive), sikap (affective),maupun keterampilan (psychomotoric) pada diriseseorang setelah menerima “inovasi” yangdisampaikan penyuluh. Penerimaan di sinimengandung arti tidak sekedar “tahu”, tetapisampai benar-benar dapat melaksanakan ataumenerapkannya dengan benar sertamenghayatinya dalam kehidupan dalam usahataninya. Penerimaan inovasi tersebut biasanyadapat diamati secara langsung maupun tidaklangsung oleh orang lain, sebagai cerminan dariadanya perubahan sikap, pengetahuan, dan atauketerampilan.
Hasil penelitian Umi, dkk (2014) menunjukanbahwa bahwa tingkat pendidikan petaniberhubungan sangat erat dan positif dengankadar adopsi teknologi Pengelolaan TerpaduKebun Jeruk Sehat (PTKJS), di mana tingkatpengetahuan selalu lebih tinggi daripada tingkatadopsi mereka. Hal ini menjelaskan bahwa tanpapengetahuan yang memadai, petani tidak dapatmengadopsi teknologi PTKJS dengan baik, ataudengan kata lain tidak mungkin suatu adopsiterwujud tanpa diawali dengan bekalpengetahuan yang memadai. Hasil penelitianUmi dkk (2014), juga mengindikasikan bahwapengetahuan petani memiliki peran yang sangatpenting dalam sebuah proses adopsi-inovasi.Oleh karena itu upaya meningkatkanpengetahuan komponen penyelenggapenyuluhan seperti petani, penyuluh ataupunpengambil kebijakan sangat penting. Dengandemikian temu inovasi pertanian sebagai sebuahmedia komunikasi antara petani-penyuluh-peneliti dan pengambil kebijakan perlu terusdilakukan, sebagaimana yang telah dilakukanoleh BPTP Bali tahun 2019-2020.
Gambar 3. Katagori pengetahuan peserta temu inovasi tahun 2019-2020 di Bali tentang teknologi pengolahanbawang merah
53
Sikap Peserta Temu Inovasi tentang TeknologiPengolahan Bawang Merah
Hasil evaluasi menunjukan bahwa sikappeserta tentang teknologi pengolahan bawangmerah berubah ke-arah yang lebih positivesetelah peserta mengikuti temu inovasi tahun
2019-2020. Pada saat pre test, sikap pesertayang berprofesi sebagai penyuluh sebanyak6,9% ragu-ragu; 66,7% setuju dan 26,4% sangatsetuju serta sama sekali yang memiliki sikapsangat tidak setuju dan tidak setuju (Tabel 4 danGambar 4). Namun sikap penyuluh tersebutberubah menjadi ragu-ragu sebanyak 2,8%;
Tabel 4. Katagori sikap peserta temu inovasi pertanian tahun 2019-2020 di Bali tentang teknologipengolahan bawang merah
Gambar 4. Katagori sikap peserta temu inovasi pertanian tahun 2019-2020 di Bali tentang teknologi pengolahanbawang merah
Perilaku Peserta Temu Teknis Inovasi Pertanian Tentang PengolahanBawang Merah | I Wayan Alit Artha Wiguna, dkk.
54 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
setuju (58,3%) dan sangat setuju (58,3%) sertajuga tidak ada yang memiliki sikap sangat tidaksetuju dan tidak setuju. Selanjutnya untuk pesertayang berprofesi sebagai birokrat (non penyuluh),sebanyak 60,0% memiliki sikap setuju dan 40,0%sangat setuju, serta tidak ada yang sangat tidaksetuju, tidak setuju ataupun ragu-ragu saat pretest. Sikap mereka berubah menjadi sangatsetuju 80,0% dan setuju 20,0% serta sama sekalitidak ada yang memiliki sikap sangat tidak setuju,tidak setuju ataupun ragu-ragu tentang teknologipengolahan bawang merah setelah mengikutitemu inovasi pertanian tahun 2019 dan 2020.Demikian pula halnya dengan sikap petani, yangsaat pre test sebagian besar (58,3%) memilikisikap setuju; 37,5% bersikap sangat setuju dantidak setuju (4,2%) serta sama sekali tidak adayang memiliki sikap sangat tidak setuju, ataupunragu-ragu saat pre test mengalami perubahanmenjadi ragu-ragu 8,3%; setuju 50,0% dansangat setuju 41,7% serta tidak ada yangbersikap sangat tidak setuju dan tidak setuju.
Mengacu pada hasil evaluasi tersebut dapatdikatakan bahwa temu inovasi pertanian yangdiselenggarakan BPTP Bali tahun 2019 dan2020, memegang peranan penting dalammeningkatkan sikap peserta ke-arah yang lebihpositive tentang teknologi pengolahan bawangmerah. Sikap terhadap perubahan menggam-barkan bentuk kesiapan dalam meresponterhadap suatu perubahan (dalam hal iniperubahan teknologi). Dalam pandangan Rogersdan Shoemaker (1971), individu anggota sistemsosial yang berorientasi pada perubahan akanselalu memperbaharui diri, terbuka pada hal-halbaru, dan giat mencari informasi. Salah satu carauntuk menumbuhkan sikap atau orientasi padaperubahan adalah dengan memilih inovasi-inovasi yang layak untuk diperkenalkan secaraberurutan. Petani yang mempunyai sikap terbukaterhadap perubahan akan mudah berinteraksidengan penyuluh pertanian. Pengalaman selamamengelola kegiatan seperti pengolahan bawangmerah akan membentuk sikap petani terhadapinovasi teknologi yang dikenalkan penyuluhpertanian. Berbagai faktor yang mempengaruhipembentukan sikap adalah pengalaman pribadi,kebudayaan, orang lain yang dianggap penting,media massa, institusi atau lembaga pendidikandan lembaga agama, serta faktor emosi di dalamdiri individu. Sikap yang diperoleh melaluipengalaman akan menimbulkan pengaruhlangsung terhadap perilaku berikutnya.
Hubungan antara Pengetahuan, Sikap danFaktor Individu Peserta Temu InovasiPertanian
Secara umum pengetahuan, sikap danfactor individu seseorang adalah salingmempengaruhi. Faktor individu yang dimaksuddalam hal ini seperti umur, Pendidikan, sertastatus sesorang dalam sebuah pekerjaan. Dalamkegiatan temu inovasi pertanian yangdilaksanakan oleh Balai Pengkajian TeknologiPertanian Bali tahun 2019 dan 2020,menganalisis factor individu peserta yaitu: (A)status usia yang dibedakan menjadi 4 katagoriyaitu: (1) usia muda kurang dari 15 tahun; (2)usia sangat productive antara 15 dan 49 tahun;(3) usia productive antara 50 dan 64 tahun dan(4) Usia tidak productive lebih dari 65 tahun.Faktor individu lainnya adalah Pendidikan yangdibedakan menjadi: (1) SD; (2) SLTP; (3) SLTA;(4) Perguruan Tinggi. Sedangkan factor individuyang berhubungan dengan pekerjaan pesertadibedakan menjadi: (1) Non fungsional; (2)Terampil: (3) Ahli Muda; (4) Ahli Madya dan (5)Ahli Utama. Faktor individu tersebut diperediksiberpengaruh terhadap pengetahuan dan sikappeserta tentang teknologi pengolahan bawangmerah, yang dibahas saat temu inovasi pertaniandi Bali tahun 2019 dan 2020. Data dianalisismenggunakan corelasi Pearson, untuk melihathubungan antara factor individu denganpengetahuan dan sikap peserta tentang teknologipengolahan bawang merah. Hasil analisismenunjukan bahwa status usia, berpengaruhnegative terhadap pengetahuan dan sikap pe-serta tentang teknologi bawang merah, sekalipunpengaruh tersebut tidak nyata pada level 5%(P>0,05) seperti ditunjukan pada Tabel 5.
Selanjutnya Tebel 5 juga menunjukan bahwasemakin tinggi tingkat pendidikan serta jenjangfungsional seseorang dalam pekerjaannyasebagai penyuluh pertanian, maka pengetahuandan sikapnya tentang teknologi pengolahanbawang merah adalah semakin baik. Faktorpendidikan berpengaruh sangat nyata pada level1% (P<0,01) terhadap pengetahuannya, namunberpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadapsikapnya tentang pengolahan bawang merah.Sedangkan jenjang fungsional berpengaruhnyata (P<0,05) terhadap pengetahuan dansikapnya tentang teknologi pengolahan bawangmerah.
Hasil analisis tersebut menggambarkan
55
bahwa semakin kurang productive usiaseseorang, maka pengetahuan mereka tentangteknologi pengolahan bawang merah akansemakin rendah. Demikian pula dengan sikappeserta akan semakin negative tentangpengolahan bawang merah dengan semakintidak produktivenya usia seseorang. Kondisitersebut dapat dipahami karena semakin tuaumur sesorang, setelah mereka memasuki usiadewasa, maka semakin rendah daya tangkapnyaterhadap sebuah teknologi inovasi yangdidiskusikan dalam kegiatan temu inovasipertanian. Sebaliknya, semakin muda usiaseseorang maka daya tangkap mereka akansemakin baik.
Daya tangkap sesorang tentang sebuahteknologi akan berdampak atau berpengaruhtehadap sikap mereka. Kemampuan sesoranguntuk menangkap atau memahami suatu materidiskusi, akan berpengaruh terhadappengetahuannya terhadap materi yangdidiskusikan. Porwadarminta (1991) menyatakanbahwa pemahaman merupakan proses berpikirdan belajar, karena untuk menuju ke arahpemahaman perlu diikuti dengan belajar danberpikir. Temu inovasi pertanian adalah sebuahmetode penyuluhan, dan penyuluhan merupakansebuah proses pendidikan non formal.Sedangkan pendidikan sendiri adalah prosesbelajar dan berpikir. Sebelumnya NgalimPurwanto (1984) menyatakan bahwapemahaman merupakan proses, perbuatan dancara memahami. Anas Sudijono (1996),menyatakan bahwa pemahaman adalahkemampuan seseorang untuk mengerti ataumemahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahuidan diingat. Oleh karena itu pemahaman dapatdikatakan adalah kemampuan seseorang untukmengetahui tentang sesuatu dan dapatmelihatnya dari berbagai segi.
Pemahaman merupakan jenjangkemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggidari ingatan dan hafalan. Dapat dimengertibahwa semakin tua umur seseorang setelahmelewati usia produktive, kemungkinankemampuanya untuk memabahami suatau objekatau materi, akan semakin rendah, sehinggapengetahuannyapun juga semakin rendah, yangberdampak pada sikap yang semakin negative.Terkait dengan hasil analisis tentang hubunganatau korelasi antara pengtahuan, sikap,pendidikan, status usia, jenjang fungsionalpenyuluh, maka sebaiknya dalam pelaksanaantemu inovasi pertanian, sedapat mungkin dipilihpeserta dengan pendidikan dan jenjangfungsional yang lebih tinggi, serta usia yangmasih muda dan produktif.
KESIMPULAN DAN SARAN
Temu inovasi pertanian yang diseleng-garakan BPTP Bali tahun 2019 dan 2020 tentangpengolahan bawang merah, mampumeningkatkan pengetahuan dan sikap pesertake-arah yang lebih baik. Temu inovasi pertaniansangat berpeluang untuk mempercepat proses-adopsi inovasi teknologi pertanian innovativehasil Balitbangtan. Pengetahuan dan sikaptentang sebuah teknologi akan dipengaruhi olehtingkat pendidikan, jenjang fungsional, dan statususia seseorang. Semakin tinggi tingkatpendidikan dan jenjang fungsional makapengetahuan mereka semakin baik, sertamemiliki sikap kea rah positive. Sedangkansemakin kurang atau tidak productive seseorangdilihat dari status usia, maka semakin rendahpengetahuan mereka tentang sebuah inovasiteknologi, dan semakin nagatip pula sikapnyaterhadap teknologi tersebut.
Tabel 5. Hubungan antara status usia, pendidikan dan jenjang fungsioanal dengan pengetahuan, sikap pesertatemu inovasi tentang pengolahan bawang merah.
Parameter Uji Corelasi Pengetahuan Sikap Status Usia Pendidikan Jenjang Fungsional
Pengetahuan 1,000 0,366** -0,062 0,233** 0,130*
Sikap 0,366** 1,000 -0,073 0,102 0,138*
Status Usia -0,062 -0,073 1,000 0,324** 0,447**
Pendidikan 0,233** 0,102 0,324** 1,000 0,757**
Jenjang Fungsional 0,130* 0,138* 0,447** 0,757** 1,000
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Perilaku Peserta Temu Teknis Inovasi Pertanian Tentang PengolahanBawang Merah | I Wayan Alit Artha Wiguna, dkk.
56 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
Sebaiknya temu inovasi untuk teknologipertanian lain, khususnya teknologi yangdihasilkan Balitbangtan dapat terus dilakukan.Karena akan berpeluang untuk mempercepatproses adopsi-inovasi pertanian dari Balitbangtankepada petani sebagai pengguna teknologi.Sedapat mungkin dalam pelaksanaan temuinovasi teknologi diupayakan pesertanya memilikitingkat pendidikan dan jenjang fungsional yanglebih tinggi, dengan usia yang masih produktif.
DAFTAR PUSTAKA
Putri, N.I. 2011. Penerapan Teknologi PertanianPadi Organik di Kampung Ciburuy(Studikasus : Kecamatan Berastagi, KabupatenKaro, Desa Ciburuy, Kecamatan Cibom-bong, Kabupaten Bogor). Skripsi. FakultasPertanian.Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Kurnia Suci Indraningsih. 2011. PengaruhPenyuluhan Terhadap Keputusan Petanidalam Adopsi Inovasi Teknologi UsahataniTerpadu. Jurnal Agro Ekonomi, Volume 29No.1, Mei 2011: 1 – 24. Pusat SosialEkonomi dan Kebijakan Pertanian Jl. A. Yani70 Bogor 16161.
Rogers, E.M., and F.F. Shoemaker. 1971.Communication of Innovations: A CrossCultural Approach. The Free Press. NewYork
Umi Pudji Astuti, D. Sugandi, Hamdan. 2014.Faktor-Faktor Yang Memengaruhi AdopsiPetani Terhadap Inovasi Teknologi JerukGerga Lebong Di Provinsi Bengkulu. BalaiPerngkajian Teknologi Pertanian BengkuluJln. Irian Km. 6,5, Bengkulu 38119 E-mail:[email protected]
Mardikanto T, Sutarni S. 1996. Petunjukpenyuluhan pertanian. Surabaya: UsahaNasional
Lubis, S. N. 2000. Adopsi Teknologi dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya. USU Press.Medan
Porwadarminta. 1991. Kamus Besar BahasaIndonesia. Balai Pustaka hlm. 636
Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan TeknikEvaluasi Pengajaran. 1984. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1984), hlm. 44
Anas Sudijono. 1996. Pengantar EvaluasiPendidikan, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1996), hlm. 50
57
POTENSI LIMBAH JAGUNG MANIS MENDUKUNG KETERSEDIAAN PAKANTERNAK SAPI BALI DI KECAMATAN KLUNGKUNG, KABUPATEN KLUNGKUNG
Ni Luh Gede Budiari1, I Nyoman Adijaya2 dan I Nyoman Sutresna3
1,2) Peneliti Balai PengkajianTeknologi Pertanian Bali3) Litkayasa Balai PengkajianTeknologi Pertanian Bali
Jln. By Pass Ngurah Rai Pesanggran Denpasar,Tlp. (0361) 720498E-mail :[email protected]
Submitted date : 22 Januari 2021 Approved date : 26 Pebruari 2021
ABSTRACT
The Potential of Sweet Corn Waste Support the Availability of Bali Beefin the Klungkung Districts
Public cattle farms are generally constrained in providing sustainable feed as a result of land conversion,as well as breeders only rely on natural feed. This results in gaps in the supply of food due to seasonal patterns,especially during the dry season. The same thing was also found in the people’s cattle business in the Klungkungarea. There fore, it is necessary to find a solution for the provision of feed during feed shortages, one of whichis the use of agricultural waste. Klungkung Regency is the center for the development of sweet corn whichproduces fresh waste.The resulting waste has the potential to be used as cattle feed.The study was carried outfor 4 months from April to August 2019. Calculation of the potential waste of sweet corn is done by doing ubinanto obtain primary data on productivity and potential waste, while the calculation of carrying capacity is calculatedusing the formula: Carrying capacity = area of land for planting sweet corn (ha) x wet weight / ha (t).Secondarydata were also used to obtain the potential of the area. The results of the analysis showed that the potential forsweet corn waste per ha was an average of 27.80 t or 63.02% of the plant’s biological yield. The potential of thiswaste, if it can be optimally utilized, will be able to meet the needs of 927 cattle weighing 300 kg a day. Thecarrying capacity of cattle with an area of 1 hectare for 1 production cycle (6 months) is 5.15 heads while forKlungkung Regency with an average planting area of 405.25 ha of sweet corn per year, the capacity of cattle is2,087 cows.
Keywords: Potential waste, sweet corn, carrying capacity, cattle
ABSTRAK
Peternakan sapi rakyat umumnya terkendala dalam penyediaan pakan secara berkelanjutan akibat dariadanya alih fungsi lahan, selain juga peternak hanya mengandalkan pakan dari alam. Hal ini berakibat adanyakesenjangan penyediaan pakan akibat pola musim khususnya pada musim kemarau. Hal serupa juga ditemukanpada usaha ternak sapi rakyat di daerah Klungkung. Oleh karena itu perlu dicarikan solusi untuk penyediaanpakan pada saat paceklik pakan, salah satunya dengan pemanfaatan limbah pertanian. Kabupaten Klungkungmerupakan sentra pengembangan jagung manis yang menghasilkan limbah segar.Limbah yang dihasilkanberpotensi dijadikan pakan ternak sapi. Kajian dilakukan selama selama 4 bulan dari bulan April-Agustus2019. Penghitungan potensi limbah jagung manis dilakukan dengan melakukan ubinan untuk mendapatkandata primer produktivitas dan potensi limbah, sedangkan perhitungan daya dukung dihitung dengan formula:Daya dukung = Luas lahan penanaman jagung manis(ha) x berat basah berangkasan/ha (t). Untuk mendapatkanpotensi wilayah juga digunakan data sekunder. Hasil analisis menunjukkan potensilimbahjagungmanis per harata-rata 27,80 t atau sebesar 63,02% dari hasil biologis tanaman. Potensi limbah ini apabila dapat dimanfaatkansecara optimal akan dapat memenuhi kebutuhan ternak sapi dengan bobot 300 kg sebanyak 927 ekor dalamsehari. Daya tampung ternak sapi dengan luasan 1 hektar selama 1 siklus produksi (6 bulan) yaitu sebesar5,15 ekor sedangkan untuk Kabupaten Klungkung dengan rata-rata luas penanaman jagung manis 405,25 haper tahun daya tampung ternak sapinya mencapai 2.087 ekor.
Kata kunci: Potensi limbah, jagung manis, daya dukung, ternak sapi
Potensi Limbah Jagung Manis Mendukung Ketersediaan Pakan Ternak Sapi BaliDi Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung | Ni Luh Gede Budiari, dkk.
58 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
PENDAHULUAN
Penyediaan pakan merupakan permasa-lahan utama dalam usaha pengembangan ternaksapi di Bali.Terbatasnya kesediaan hijauan pakanakibat alih fungsi lahan dan untuk kebutuhanpenyediaan pangan sehingga kondisi iniberimplikasi terhadap semakin berkurangnyaketersediaan lahan pertanian karena lahanpertanian dikonversi menjadi ruang untukpengembangan pemukiman dan berbagaikebutuhan hidup manusia lainnya. Selain faktorketerbatasan lahan, usaha peternakan sapi jugahanya mengandalkan pakan dari alam saja.Halini sesuai dengan Bamualim (2010) yangmenyatakan peternakan rakyat umumnya hanyamengandalkan ketersediaan pakan dari alamsaja dengan ketersediaan sangat tergantungpada pola musim. Pada musim kemarau produksirumput lapangan sangat terbatas dan mutunyasangat rendah dengan kandungan serat kasarhijauan meningkat sehingga zat-zat makananesensial seperti protein, energi, mineral menjadiberkurang dalam proses pencernaan danmetabolisme. Khuluq(2012) menyatakanpemberian hijauan yang berkualitas rendah dapatmenurunkan kecernaan pakan dan terjadinyadefisiensi nutrient.
Rendahnya mutu pakan akibat tingginyaserat kasar menyebabkan mikroba pencernatidak bekerja optimal. Konsekuensinya padamusim kemarau terjadi penurunan konsumsipakan yang berakibat menurunnya bobot badanternak sebesar 0,15 kg sampai 0,27 kg/ hari(Bamualim, 2010). Mastika (2009) menjelaskanbahwa tidak cukupnya ketersediaan jumlah dankualitas bahan makanan ternak dalam siklustahunan merupakan faktor yang seringmempengaruhi pertumbuhan sapi Bali.Zulbardiet al. (2000) melaporkan bahwa dalampemberian hijauan pakan ternak sebaiknyadikombinasikan antara rumput, hijauan danlegume, dimana pakan sapi penggemukandianjurkan mengandung protein kasar (PK)minimum 12%. Lebih lanjut Tillman et al (1991)melaporkan bahwa kebutuhan protein kasaruntuk pertumbuhan penggemukan sapi mudasebesar 12,6% - 15,6%.Singgih et al. (2016)melaporkan apabila kandungan PK dibawah 7%akan menyebabkan aktivitas mikroba dalamrumen menurun sehingga kecepatanpencernaan akan berkurang.
Kondisi ini terjadi pada usaha ternak sapi diKabupaten Klungkung. Ketersediaan hijauanmakanan ternak sangat tergantung padaketersediaan alam, pada musim hujanketersediaan pakan berlebihan sedangkan padamusim kemarau akan kekurangan pakan olehkarena itu alternatif penyediaan pakanternakdengan memanfaatkan limbah pertanian,seperti limbah jagung manis. Saat ini limbahjagung manis belum dimanfaatkan secaraoptimal untuk pakan ternak. Yasa (2014)menyatakan limbah jagung manis memilikipotensi untuk dimanfaatkan sebagai pakanternak sapi. Dilaporkan bahwa kandungan gizidari berangkasan tanaman jagung manis cukupbaik, dengan kandungan protein kasar berkisarantara 9,68% sampai 13,99% lebih tinggidibandingkan kandungan gizi rumput raja.Dijelaskan pemberian 50% limbah jagung untukmensubstitusi rerumputan dikombinasikandengan pakan penguat dan pemacu tumbuhmenghasilkan pertambahan berat badan harianmencapai 0,56 kg/hari, dan secara ekonomismemberikan peningkatan keuntungan mencapai28%. Untuk mengetahui potensi limbah jagungsebagai daya dukung bagi ketersediaan pakanternak sapi maka perlu dilakukan perhitungandan estimasi dalam jumlah ternak yang bisadipelihara di Kabupaten Klungkung.
METODOLOGI
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di daerah sentrapengembangan jagung manis di KecamatanKlungkung, Kabupaten Klungkung, Bali selama4 bulan dari bulan April-Agustus 2019.Pengumpulan data dilakukan dengan melakukanubinan pada jagung petani saat panen denganukuran ubinan 3,2 m x 2,4 m (7,68 m2). Setiappetani dilakukan 3 ubinan sehingga selama 5bulan pelaksanaan penelitian dilakukan 15ubinan dengan rincian:
• Panen bulan April 3 ubinan• Panen bulan Mei 3 ubinan• Panen bulan Juni 3 ubinan• Panen bulan Juli 3 ubinan• Panen bulan Agustus 3 ubinan
59
Pengumpulan Data
Data Primer
Data primer yang dikumpulkan adalah dataagronomis tanaman yaitu berat tongkol ekonomisdan berat berangkasan. Data berat berangkasantanaman selanjutnya dipakai untuk mengukurdaya dukung limbah untuk pakan ternak sapi.Berat tongkol ekonomis tanaman jagung manisdihitung dengan formula:
Sedangkan perhitungan berat berangkasan yangdihasilkan dihitung dengan formula:
Daya dukung jerami jagung manis dihitungdengan formula:
Daya dukung limbah(t) = Luas lahanpenanaman jagung manis(ha) x B.B.Berangkasan/ha (t)
Sedangkan daya dukung limbah untukpakan dihitung dengan formula:
Keterangan:X : Daya dukung limbah untuk pakan ternak
sapi (ekor)A : Berat berangkasan jagung/hektar (kg)B : Kebutuhan ternak sapi/hari (kg/ekor)
Daya Tampung Ternak Sapi (DTTS) = jumlahproduksi limbah/tahun :konsumsi pakan/siklus
Data sekunder
Menggunakan data BPS untuk mengetahuitata guna lahan serta luas lahan penanamanjagung di Kabupaten Klungkung.
Analisis data
Data dianalisis deskriptif sesuai denganvariabel yang diamati serta perhitungan terhadapdukung limbah dan daya tampung ternak sapi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Daya Dukung Limbah Jagung Manis SebagaiPakan
Hasil ubinan yang dilakukan pada petanijagung di Subak Gelgel selama 5 bulan dari bulanApril sampai dengan Agustus memberikangambaran hasil ekonomis dan limbah yangdihasilkan pada usahatani jagung manis. Hasilekonomis berkisar antara 15,86 t/ha– 17,90 t/hasedangkan limbah yang dihasilkan berupaberangkasan berkisar antara 25,82 t/ha – 29,43t/ha. Rata-rata potensi hasil ekonomis berupatongkol yaitu 17,02 t/ha sedangkan limbahberupa berangkasan tanaman dengan rata-rata27,80 ton/hektar. Hasil ekonomis berupa tongkolkupas sebesar 37,97 %, sedangkan limbahberupa berangkasan sebesar 62,03 % (Tabel 1).Hal ini menunjukan limbah jagung manis memilikipotensi sebagai penyedia pakan ternak sapi.Umela dan Bulontio. (2016) melaporkan bahwapengembangan pertanian melalui programintensifikasi pertanian untuk menjaga ketahananpangan menyebabkan peningkatan produksipangan sekaligus peningkatan limbah pertanian,hal ini berdampak pada meningkatnyaketersediaan hijauan pakan ternak.
Tabel 1. Berat tongkol ekonomis dan berangkasanjagung manis per hektar di Subak GelgelKecamatan Klungkung KabupatenKlungkung Tahun 2019
Bulan Berat tongkol Berat berang-ekonomis/ha (t) kasan/ha (t)
April 15,86 25,82Mei 16,95 27,86Juni 16,58 26,65Juli 17,90 29,43Agustus 17,82 29,21
Jumlah 85,11 138,98
Rata-rata 17,02 27,80
Keterangan: Data ubinan
Limbah jagung manis terdiri dari daun,batang dan kelobot yang merupakan bagianterbesar dari tanaman jagung itu sendiri. Limbahtanaman jagung manis masih memiliki potensiyang cukup besar dalam penyediaan pakan di
Potensi Limbah Jagung Manis Mendukung Ketersediaan Pakan Ternak Sapi BaliDi Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung | Ni Luh Gede Budiari, dkk.
60 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
wilayah kecamatan Klungkung. Hal inidisebabkan karena wilayah KecamatanKlungkung merupakan sentra pengembanganjagung manis di Bali. Penggunaan limbah jagungmanis oleh petani hanya memanfaatkan batangatas pohon jagung sebagai pakan, sedangkanbatang bawahnya belum dimanfaatkan secaraoptimal. Potensi berangkasan jagung manis inicukup banyak sekitar 34%nya masih tertinggaldi lahan yang berpotensi mampu mendukungpenyediaan pakan 5 ekor/tahun dan secaraekonomis, nilai jual berangkasan terbuangmencapai Rp.6.000.000,-sampai Rp. 6.600.000,-(Yasa., et al 2014).
Jika dilihat potensi dengan memadukan dataprimer dengan data sekunder luas penanamanjagung manis di Kabupaten Klungkung makaterlihat potensi berat tongkol ekonomis dan beratberangkasan segar yang dihasilkan dariusahatani jagung manis yang dilakukan. DistanKlungkung (2020) mendata luas penanamanjagung manis di Kabupaten Klungkungmengalami peningkatan pada tahun 2018 dansetelahnya mengalami penurunan. Potensitongkol ekonomis dan berangkasan yangdihasilkan dengan menggunakan asumsi rata-rata hasil/hektar data primer tahun 2019 dikalikandengan luas lahan penanaman jagung manis di
Kabupaten Klungkung. Rata-rata dalam setahunjumlah tongkol ekonomis dan berangkasan segaryang dihasilkan dari usahatani jagung manismencapai 6.897 t dan 11.266 t (tabel 2)
Limbah jagung manis dapat diberikan secaralangsung pada ternak sapi dan dapat jugadiberikan dalam bentuk pakan olahan seperti haydan silase. Penggunaan pakan hay dan silasedapat diberikan pada saat musim kering, dimanaproduksi rumput sudah menurun. Santosa (2017)menyatakan jumlah daya dukung pakanber-gantung terhadap jumlah hasil produksipertanian tanaman pangan dan luas arealperkebunan. Semakin tinggi jumlah hasilproduksi dan luas areal pertanian, semakin tinggipula daya dukung pakan mendukung populasiternak sapi.
Karakteristik dari limbah pertanian adalahterdapat kandungan se-lulosa dan hemiselulosadimana ru-men sapi mempunyai mikroba yangdapat menghasilkan enzim-enzim sehinggadapat dimanfaatkan untuk energi dan protein bagisapi melalui fermentasi dalam rumen tersebut(Tanuwiria, dkk., 2006). Berdasarkan analisaproksimat kandungan nutrisi dari limbah jagungcukup tinggi, terutama pada kelobot mini(Tabel3). Kandungan nutrisi dari limbah jagungini dapat menjadikan limbah jagung sebagai
Tabel 2. Luas tanam, berat tongkol ekonomis dan berangkasan jagung manis di Subak Gelgel KecamatanKlungkung Kabupaten Klungkung Tahun 2017-2020
Tahun Luas tanam (ha)* Berat tongkol ekonomis/ha (t) Berat berangkasan/ha (t)
2017 458,00 7.795 12.7322018 550,00 9.361 15.2902019 355,50 6.051 9.8832020 257,50 4.383 7.159
Jumlah 1621,00 27.589 45.064
Rata-rata 405,25 6.897 11.266
Keterangan: * Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung- Data primer diolah
Tabel 3. Analisis kandungan nutrisi jerami jagung manis di Kabupaten Klungkung, Bali Tahun 2014
Nama Bahan Pakan BK (%) Abu (%) SK (%) PK (%) LK(%) BETN (%)
Batang jagung 91,59 11,04 33,00 9,72 2,48 68,34Kelobot jagung 90,51 5,59 19,00 11,87 2,79 70,27Kelobot mini 93,25 5,56 15,00 13,92 4,39 69,37
Keterangan : Hasil analisis proksimat laboratorium nutrisi pakan ternak, Fakultas Peternakan, UniversitasUdayana.
61
pengganti rumput. Budiari et al. (2014)menyatakan sapi yang diberikan pakan jeramijagung manis yang dicampur dengan rumputmenghasilkan pertambahan bobot badansebesar 0,45 kg/ekor/hari. Hasil penelitianBudiari et al. (2019) mendapatkan pemanfaatantepung jagung dan kacang tanah untukpenggemukan sapi Bali mampu mensubstitusi50% pemberian dedak padi tanpa menurunkanpertambahan bobot harian ternak dengan rata-rata pertambahan berat harian ternak 0,50 kg/hari. Sapi yang diberikan pakan dasar limbahjagung manis ditambah 1 kg pollard/ekor/hari dandiinjeksi pemacu tumbuh 1ml/90 bobot badanmenghasilkan pertambahan bobot badan 0,60kg/ekor/hari.
Untuk memenuhi kebutuhan pakan ternaksapi petani memberikan campuran antara hijauandan limbah jagung manis. Zulbardi et al. (2000)melaporkan bahwa dalam pemberian hijauanpakan ternak sebaiknya dikombinasikan antararumput, hijauan dan legume, dimana pakan sapipenggemukan dianjurkan mengandung proteinkasar (PK) minimum 12%. Sukaryani danMulyono (2018) menyatakan ketersediaan bahanpakan secara kontinyu baik kuantitas dan kualitasmenjadi faktor pendukung dalam upayapeningkatan produktivitas ternak. Kualitas pakanyang baik akan digunakan untuk kebutuhanhidup pokok dan berproduksi. Tillman et al.(1991) menyatakan kecernaan pakan sangattergantung dari keseimbangan zat-zat nutrisidalam ransum. Kebutuhan nutrisi setiap ternaktergantung pada jenis ternak, umur, kondisitubuh(normal, sakit) dan lingkungan tempathidupnya (temperatur, kelembaban nisbi udara),
fase (pertumbuhan, dewasa, bunting, menyusui),serta bobot badannya (tabel 4).
Partama et al. (2011) melaporkan bahwauntuk mendapatkan tingkat konsumsi yangoptimal diperlukan formula ransum yang sesuaidengan kebutuhan ternak yaitu ransum yangmengandung nutrien yang cukup dan seimbang.Untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak tidakcukup dengan mengkonsumsi satu jenis hijauansaja, Oleh karena itu pemberian campuran dariberbagai jenis hijauan dapat memenuhikebutuhan gizi dari ternak. Kandungan gizi darisatu hijauan pakan itu tidak sama dengan hijauanlainnya, dengan pemberian campuran hijauanpakan maka antara satu hijauan akan salingmelengkapi kandungan gizinya.
Daya Tampung Ternak Sapi
Perhitungan mengenai kapasitas tampungsuatu lahan terhadap jumlah ternak yangdipelihara adalah berdasarkan pada produksihijauan pakan yang tersedia. Dalam perhitunganini digunakan norma Satuan Ternak(ST) yaituukuran yang digunakan untuk menghubungkanbobot badan ternak dengan jumlah pakan yangdikonsumsi (Delima et al., 2015).Umela danBulontio. (2016) melaporkan bahwa kebutuhannutrisi seekor sapi dewasa satu satuan ternak(ST) adalah setara 2,2813 ton BK per tahun atau1,5695 ton TDN per tahun. Daya dukung limbahjagung manis yang dihasilkan diperoleh denganmembagi jumlah limbah (berangkasan tanamanjagung manis) dengan kebutuhan pakan hijauanternak per ekor per hari.
Menggunakan asumsi berat sapi 300 kgmaka dibutuhkan 30 kg pakan per hari. Dayadukung limbah berangkasan jagung manis yaitusebesar 27,80 t/hektar atau 27.800 kg akan dapatmencukupi kebutuhan ternak sapi sebanyak 927ekor. Sedangkan untuk daya tampung ternaksapi selama 1 siklus pemeliharaan (asumsi 6bulan), maka limbah berangkasan jagung manistersebut akan mampu mencukupi kebutuhanternak sapi sebanyak 5,15 ekor. Dengan rata-rata luas penanaman jagung manis 405,25 ha,maka daya tampung ternak sapi denganmemanfaatkan pakan dari berangkasan jagungsebanyak 2.087 ekor (tabel 5).
Ketersediaan hijauan makanan ternak(rumput alam dan limbah tanaman pangan)sangat tergantung pada ketersediaan lahan.Kabupaten Klungkung memiliki lahan yang
Tabel 4. Kebutuhan nutrisi pakan untuk ternakpembibitan dan penggemukan.
Tujuan ProduksiUraian (%)
Pembibitan Penggemukan
Kadar Air 12 12Bahan Kering 88 88Protein Kasar 10,4 12,7Serat Kasar 19,6 18,4Lemak Kasar 2,6 3Kadar abu 6,8 8,7Total Digestible Nutrien 64,2 64,4(TDN)
Sumber :Wahyono (2000)
Potensi Limbah Jagung Manis Mendukung Ketersediaan Pakan Ternak Sapi BaliDi Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung | Ni Luh Gede Budiari, dkk.
62 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
sangat luas yang dapat mendukung ketersediaanhijauan pakan. Penyediaan pakan secaraberkesinambungan dari segi kualitas dankuantitas merupakan faktor utama dalam upayapeningkatan produktifitas ternak. Pemanfaatanlimbah pertanian merupakan solusi untukpenyediaan pakan secara berkelanjutan dandapat mengurangi sebagian atau seluruh hijauanserta dapat mengurangi ketergantungan padapenggunaan bahan konsentrat. Yusdja danIlham. (2006) melaporkan bahwa penurunanproduksi pakan akan mempengaruhi dayadukung ternak untuk menyediakan pakan,bahkan menyebabkan penurunan populasi.Ketersediaan pakan merupakan faktor utamadalam menentukan daya tampung ternak di suatuwilayah.
KESIMPULAN
Potensi limbah jagung manis per ha sebagaipakan ternak sapi rata-rata 27,80 t atau sebesar63,02% dari hasil biologis tanaman jagung manis.Potensi limbah ini apabila dapat dimanfaatkansecara optimal dapat memenuhi kebutuhanternak sapi dengan bobot 300 kg sebanyak 927ekor dalam sehari. Daya tampung ternak sapidengan luasan 1 hektar selama 1 siklus produksi(6 bulan) yaitu sebesar 5,15 ekor sedangkanuntuk Kabupaten Klungkung dengan rata-rataluas penanaman jagung manis 405,25 ha pertahun daya tampung ternak sapinya mencapai2.087 ekor.
DAFTAR PUSTAKA
Bamualin, M.A. 2010. Pengembangan TeknologiPakan Sapi Potong di Daerah Semi AridNusa Tenggara. Materi PengukuhanProfesor Riset Bidang pemuliaan
Ruminansia (Pakan dan Nutrisi Ternak).Bogor, 29 Nopember 2010. Badan Penelitiandan Pengembangan Pertanian. Jakarta.
Budiari, N.L.G., I.M.Raiyasa, dan I.P.A.Kertawirawan. 2014. PeningkatanProduktivitas Sapi Bali Dara DenganPemanfaatan Limbah Jagung Manis.Prosiding. Seminar Nasional PembangunanNasional Berbasis Teknologi danSumberdayaLokal. Kerjasama LPPMdengan Fakultas Pertanian, UniversitasMuhammadiyah Jember. Jember 19 Agustus2014. Hlm 54 – 58
Budiari NLG, Kertawirawan IPA, Adijaya IN,Sugianyar IM. 2019.Substitution of rice branwith soil bean skin to increase the growth ofcows in Buleleng District, Bali. Proceedingof The 2nd International on Food andAgricuture.Bali Nusa Dua 2nd-3rd 2019.Jember (Indonesia): Politeknik NegeriJember. p. 322-328.
Delima, M., Karim, A., &Yunus, M. (2015). Kajianpotensi produksi hijauan pakan pada lahaneksisting dan potensial untuk meningkatkanpopulasi ternak ruminansia di kabupatenAceh Besar. Jurnal Agripet, 15(1), 33-40.
Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung. 2020.Data Luas Tanam Jagung Manis diKabupaten Klungkung Tahun 2017-2020.Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung.
Khuluq AD. 2012. Potensi pemanfaatan limbahtebu sebagai pakan fermentasi probiotik.Buletin Tanaman Tembakau, Serat danMinyak Industri, 4(1): 37-45.
Mastika. I. M. dan A.W. Puger. 2009. UpayaPerbaikan Penampilan (Performance) SapiBali Melalui Perbaikan Ketersediaan danKualitas Pakan. Makalah Disampaikan padaSeminar Sapi Bali di Unud dalam Rangka
Tabel 5. Daya dukung dan daya tampung ternak sapi dengan memanfaatkan limbah dari berangkasan jagungmanis untuk pakan di Kabupaten Klungkung
Uraian Jumlah
Berat berangkasan jagung manis/hektar 27,80 tonKebutuhan pakan ternak sapi/ekor/hari asumsi berat ternak 300 kg (10% dari berat badan) 30 kgDaya dukung berangkasan jagung manis untuk pakan per hektar 927 ekorDayaTampungTernak Sapi (DTTS) (siklus 6 bulan pemeliharaan) per hektar 5,15 ekorDayaTampungTernak Sapi (DTTS) (siklus 6 bulan pemeliharaan) Kabupaten Klungkung 2.087 ekor
Keterangan: data primer diolah
63
Perayaan Dies Natalis Unud ke 47, padaTanggal 5-6 Oktober 2009, di Kampus PusatSudirman Denpasar.FakultasPeternakan,Universitas Udayana. 12 hal.
Santoso, A. B., & Nurfaizin, N. (2017). ProyeksiDaya Dukung Pakan dan Populasi Sapi diProvinsi Maluku. Agriekonomika, 6(1), 1-11.
Singgih Setyawan, Irfan R. Hidayat, dan DwiYulistiani. 2016. Ketersediaan HasilSampingTanaman Tebu Di Provinsi JawaBarat dalam Mendukung KetersediaanPakan Ternak Ruminansia. Prosiding.Seminar Nasional dan Ekspose InovasiTeknologi BPTP Jawa Tengah “PenyediaanInovasi dan Strategi Pendampingan untukPencapaian Swasembada Pangan”Kabupaten Semarang. Hal. 1051 -1058
Sukaryani S, Mulyono AM. 2018. Bioteknologifermentasi jerami padi dengan Aspergillusniger dan Trichoderma AA1 terhadapproduksi gas NH 3 dan VFA. In PemanfaatanSumber Daya Lokal Menuju KemandirianPangan Nasional. Sukoharjo (ID):Universitas Veteran Bangun Nusantara.Hlm. 229-234.
Tanuwiria, U. H., Yulianti, A., & Mayasari, N.(2006). Potensi pakan asal limbah tanamanpangan dan daya dukungnya terhadappopulasi ternak ruminansia di wilayah
Sumedang (Agriculture by product aspotential feed and its carrying capacity InSumedang). Jurnal IlmuTernak, 6(2), 112-120.
Tillman AD, Hartadi H, Reksohadiprodjo S,Prawirokusumo S, Lebdosukojo S. 1991.Ilmu makanan ternak dasar. Gajah MadaUniversity Press. Yogyakarta.
Umela, S., & Bulontio, N. (2016). Daya dukungjerami jagung sebagai pakan ternak sapipotong. Jurnal Technopreneur (JTech), 4(1),64-72.
Yasa. I.M.R., A.A.N.B. Kamandalu, I.N. Adijaya,N.L.G. Budiari, dan P.A. Kertawirawan. 2014.Laporan Akhir Model Penggemukan SapiBali Terintegrasi dengan Tanaman JagungManis di Kabupaten Klungkung Bali. BalaiPengkajian Pertanian Bali. Denpasar.
Yusdja Y dan N. Ilham. 2006. Arah KebijakanPembangunan Peternakan Rakyat. AnalisisKebijakan Pertanian 2 (2) : 183 – 203.
Zulbardi M, Kuswandi, Martawidjaja M,Thalib C,Wiyono DB. 2000. Daung liricidiasebagaisumber protein pada sapi potong.Prosiding Seminar Nasional Peternakan danVeteriner. Bogor, 18-19 September 2000..Bogor (Indonesia): Pusat Penelitian danPengembangan Peternakan. Hlm. 233 -241.
Potensi Limbah Jagung Manis Mendukung Ketersediaan Pakan Ternak Sapi BaliDi Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung | Ni Luh Gede Budiari, dkk.
64 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
TINGKAT EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN WARU (Hibiscus tiliaceus) TERHADAPPARASIT GASTROINTESTINAL PADA SALURAN PENCERNAAN KAMBING
PERANAKAN ETTAWAH (PE) DI DESA SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM
I Wayan Sudarma1 dan A.A.N. Badung Sarmuda Dinata2
1,2)Penelti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BaliJl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar, PO BOX 3480 telp/fax: (0361) 720 498
E-mail:[email protected]
Submitted date : 22 Januari 2021 Approved date : 26 Pebruari 2021
ABSTRACT
Effectiveness Level of Waru Leaves (Hibiscus tiliaceus) Extract to GastrointestinalParasites at Ettawah (PE) Cross Breeding in Sidemen Village, Karangasem Regency
Research on the use of waru leaf extract as a worm medicine has been carried out, the research wasconducted in the farmer group “Menaka Giri”, Sidemen village, Sidemen district, Karangasem Regency fromJuly to August 2020 against 20 male goats (PE) aged 7 months, divided into 4 treatments. with 5 heads each asa replication, namely P0 (goat livestock without waru leaf extract), P1 (goat livestock with waru leaf extract 25cc/ head/day), P2 (goat livestock with waru leaf extract dose of 50 cc/head/days) and), P3 (goat livestock withextract of waru leafdose of 75 cc/head/day). The results showed that all of the goats were infected with 5 typesof worms in the form of nematode worms (Haemonchus sp,Strongylus sp and Strongyloides sp andTrichostrongylus sp) and trematoda worms (Bonustomum sp). The anthelmintic power of hibiscus leaf extractat the level of 50 cc/head/day is quite effective in killing nematode worms up to 35% compared to the 25 mg/head/day of waru leaf extract and the level of 75 cc/head/day only 27% and 30%. The anthelminthic power ofhibiscus leaf extract against worm eggs can suppress up to 32% while at the level of 25 cc/head/day and 75 cc/head/day respectively 28% and 30%.
Keywords: Goat (PE), gastrointestinal parasites, waru leaf extract
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian pemanfaatan ekstrak daun waru sebagai obat cacing, penelitian dilakukan diKelompok Tani “Menaka Giri” Desa Sidemen Kecamatan SidemenKabupaten Karangasem pada bulan Julihingga Agustus 2020 terhadap Kambing (PE) jantan umur 7 bulan sebanyak 20 ekor, terbagi dalam 4 perlakuandengan masing-masing 5 ekor sebagai ulangan yaitu P0 ( ternak kambing tanpa ekstrak daun waru),P1 (ternakkambing dengan ekstrak daun waru 25 cc/ekor/hari),P2 (ternak kambing dengan ekstrak daun waru dengandosis 50 cc/ ekor/hari )danP3 (ternak kambing dengan ekstrak daun waru dengan dosis 75 cc/ekor/hari ).Hasilmenunjukkansecara keseluruhan kambing terinfeksi 5 jenis cacing berupa cacing nematoda (Haemonchus sp,Strongylus spdan Strongyloides sp dan Trichostrongylus sp ) dan cacing trematoda ( Bonustomum sp). Dayaanthelmintik ekstrak daun waru level 50 cc/ekor/hari cukup efektif membunuh cacing nematoda hingga 35%dibanding ekstrak daun waru 25 mg/ekor/hari dan level 75 cc/ ekor/ hari hanya27%dan 30 % Daya antelminthikekstrak daun waru terhadap telur cacing mampu menekan hingga 32 % sedangkan pada level 25 cc/ekor/haridan 75 cc/ekor/hari masing-masing sebesar 28% dan 30%.
Kata kunci: Kambing (PE),parasit gastrointestinal,ekstrak daun waru
65
PENDAHULUAN
Desa Sidemen merupakan salah satu desayang berada di Kecamatan Sidemen KabupatenKarangasem memiliki topografi desa padadaerah perbukitan diketinggian 500-700mdpldengan curah hujan cukup tinggi, memilikiluasan wilayah sebesar 35,15 km 2,sertaluasanlahan sebesar 3.515 Ha. Dari luasan tersebutberupa lahan sawah 20,5 Ha dan lahankebun114,37 Ha, pemanfaatan lahan olehmasyarakat digunakan untuk berbudidaya ternakdiantaranya sapi, kambing, babi,itik danayam.Kecamatan Sidemen merupakan luasanterkecil dari 8 kecamatan lainnya berada diKabupaten Karangasem yakni sekitar 4,79%(BPS Karangasem,2019).
Seiring bertambahnya jumlah pendudukdandisisi lain Bali merupakan ikon tujuanpariwisata dimana permintaan kebutuhan daging(sapi,kambing,itik maupun ayam) setiaptahunnya mengalami peningkatan,namunsebaliknya pemenuhan kebutuhan daging belumterpenuhi bahkan masih melakukan impor dagingdari luar. Peluang pemenuhan kebutuhan dagingsebagai protein hewani dari ternak dapattermanfaatkan melalui pengembangan sektorpeternakan dengan pengembanganternakkambing Peranakan Ettawah (PE) jantan.Kambing PE jantan sebagai ternak kambingtriguna memiliki keunggulan mampu beradaptasidalamkondisi ekstrim, dapat tumbuh lebih cepat,dan memiliki perototan yang cukup baik denganpertambahan bobot badan 50-100gram/hari,(Sutama dan Budiarsana, 2009). Ditinjau aspekmanajemen, salah satu faktor penentukeberhasilan dalam budidaya kambing PE jantanyakni faktor kesehatan.
Salah satu penyakit parasitik yangseringmengganggu saluran pencernaan berupapenyakit cacingan.Penyakit cacingandapatmenimbulkan kerugian cukup besar bagipeternakyang ditandai terjadinya penurunanberat badan yang ditimbulkan, rata-rata untukkambing adalah sebesar 5 kg/ekor per penderitaper tahun (Anon, 2007). Gejala klinis yangditimbulkan berupa nafsu makan menurun, perutbuncit, ternak mengalami penurunan berat badan(kurus), bulu kurang mengkilap, pertumbuhanternak menjadi terhambat, karkas kelihatanpucat,terjadi diare, pola pemeliharaan menjadilebih lama walaupun penyakit cacingan tidaklangsung menyebabkan kematian akan tetapi
kerugian dari segi ekonomi cukup besar(Colin,1999). Upaya mengatasi penyakitcacingan pada kambing dapat dilakukan denganmenggunakan pengobatan secara herbal berupatanaman obat salah satunya dengan tanamanwaru (Indah dan Darwati, 2013 ).
Di Bali, penggunaan tumbuhan sebagai obattradisional telah lama dipercayai. Masyarakat Balimenggunakan tumbuhan sebagai obatberlandaskan pada naskah lontar usada(Nala,1993). Tumbuhan waru merupakan salahsatu jenis tumbuhan dalam Usada Taru Permanayang mengandung khasiat obat. Tumbuhan waruyang termasuk dalam suku Malvaceae denganmarga Hibiscus (Backer dan Backhuizen, 1968)digunakan dalam berbagai pengobatan.Kamarajet al. (2011) menyatakan dalam memilih bahanalam yang memiliki sifat antelmintik disarankandimana bahan tersebut mengandung bahan aktifseperti saponin, tanin, flavonoid, dan alkaloid.Daun waru dapat digunakan untuk mengobatiTBC, paru-paru, batuk, sesak napas, radangamandel (tonsillitis), demam, diare berdarah/berlendir, disentri pada anak, muntah darah,radang usus, bisul, abses, mengatasi rambutrontok dan cacingan (Indah dan Darwati, 2013).
Disamping itu, daun waru juga mengandungsenyawa polifenol, saponin dan flavonoidsertaakar waru mengandung senyawa tanin, saponin,dan flavonoid (Kumar et al., 2008:Syamsuhidayatdan Hutapea, 1991).Penelitian ini bertujuan untukmengetahui tingkat efektivitas ekstrak daun waruterhadap tingkat prevelensi,jenis cacing danjumlah telur cacing serta analisa ekonomi padasaluran pencernaan kambing PE yang di peliharadi dalam kandang panggung.
METODOLOGI
Telah dilakukan penelitian terhadap 20 ekorkambing Peranakan Ettawah (PE) jantanberumur 7 bulan berat rata -rata 35-40 kg denganwarna bulu beragam (putih, coklat, hitam, lorengputih coklat, maupun putih hitam) di KelompokTani “Menaka Giri” yang berlokasi di DesaSidemen Kecamatan Sidemen KabupatenKarangasem. Kambing PE dipelihara selama 5bulan dalam kandang panggung sebanyak 2 unit,dimana untuk 1 unit kandang berukuran 10 m x1,15 m bersekat dengan bilah bambu sertaberatap asbes. Dibagian depan kandangdilengkapi dengan tempat pakan serta dalam
Tingkat Efektitivitas Ekstrak Daun Waru (Hibiscus tiliaceus) terhadap Parasit GastrointestinalPada Saluran Pencernaan Kambing Peranakan Ettawah ..... | I Wayan Sudarma, dkk.
66 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
kandang dilengkapi dengan ember sebagaitempat muinum. Pakan utama yang diberikanberupa pakan leguminosa (gamal, lamtoro dannangka), rumput gajah serta pakan tambahanberupa dedak padi. Disamping itu dalampenelitian ini menggunakan bahan-bahan berupatimbangan, sendok makan, plastik label, pisau,plastik kantong, formalin 70%, air bersih, spidol.
Penelitian ini menggunakan RancanganAcak Kelompok (RAK) 4 perlakuan denganmasing-masing 5 ekor sebagai ulangan. Daunwaru yang digunakan yakni daun yang telahdewasa (tidak kuning, tidak terlalu tua) sebanyak8 kg lalu dijemur hingga kering dibawah terik sinarmatahari. Selanjutnya daun waru dihancurkan/ditepungkanlalu dicampur air sebanyak 4000 ml,inilah yang menjadi ekstrak air untuk diberikanpada perlakuan (Beriajayaet al., 2005).Selanjutnya ekstrak daun waru disaring dandidiamkan selama 12 jam, ekstrak daun warusiap diberikan pada ternak kambing. Sebelumdilakukan pengambilan sampel segarfeses,terlebih dahulu dilakukan pengenceran terhadapformalin 70% dengan melakukan pengenceran109 selanjutnya cairan formalin dimasukkan padatiap kantung plastik yang telah diberi label.Pengambilan sampel feses segar kambingdilakukan selama 4 kali yakni pada awal sebelumperlakuan, 2 minggu, 5 minggu dan 7 minggusetelah perlakuan.Dosis penggunaan ekstrakdaun waru diberikan dalam bentuk suspensi(cairan) lewat air minum yang terbagi sesuaidengan taraf perlakuan yakni:P0 = Ternak kambing PE + tanpa ekstrak
daun waruP1 = Ternak kambing PE + cairan ekstrak
daun waru 25 cc/ekor/hariP2 = Ternak kambing PE + cairan ekstrak
daun waru 50 cc/ekor/ hariP3 = Ternak kambing PE + cairan ekstrak
daun waru 75 cc/ekor/hariParameter yang diamati dalam penelitian
berupa tingkat prevelensi cacing yangmenyerang kambing PE, jenis cacing yangmenginfeksi kambing PE, jumlah telur cacingmenginfeksi kambing PE serta tingkat ekonomisterhadap dampak penggunaan ekstrak daunwaru.Data yang diperoleh dianalisis dengansidikragam dengan tingkat kesalahan 1-5%. Apabilapengujian sidik ragam menunjukkan pengaruhperbedaan yang nyata, maka pengujian diantararataan empat perlakuan dilakukan dengan ujijarak berganda dari Duncan. Untuk mengetahui
hubungan antara variabel dependen (Y) danvariabel independen (X) dalam pembahasandigunakan analisis regresi (Steel dan Torrie,1990).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanaman waru merupakan tumbuhan aslidari daerah tropis di Pasifik Barat. Namun, saatini telah tersebar luas di seluruh wilayah Pasifikdan dikenal dengan berbagai sebutan misalnyahau (Hawaii), purau (Tahiti), beach hibiscus,tewalpin, sea hibiscus, maupun coastalcottonwood. Daun waru memiliki kandungan gizidan nutrisi berupa protein, karbohidrat, kalsium,vitamin B1, vitamin B12, vitamin C, vitamin E,vitamin A, vitamin K, magnesium, zat Besi danasam askorbat (Syamsuhidayat and Hutapea,1991).
Tanaman waru merupakan tumbuhan yangdapat tumbuh dipantai tidak berawa, ditanahdatar, dan di pegunungan hingga ketinggian 1700mdpl. Tanaman ini banyak ditanam di pinggirjalan dan di sudut pekarangan sebagai tandabatas pagar, dimana tanaman ini dapat tumbuhhingga tinggi 5-15 meter, dengan garis tengahbatang 40-50 cm, bercabang dan berwarnacoklat. Tanaman waru memiliki daun tunggal,berangkai, berbentuk jantung, lingkaran lebar/bulat telur, tidak berlekuk dengan diameterkurang dari 19 cm, memiliki bentuk daun menjari,sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjarberbentuk celah pada sisi bawah dan sisipangkal. Sisi bawah daun berambut abu-aburapat. Daun penumpu bulat telur memanjang,panjang 2,5 cm, meninggalkan tanda bekasberbentuk cincin.Bunga waru merupakan bungatunggal, bertaju 8-11. Panjang kelopak 2,5 cmberaturan bercangap 5. Daun mahkota berbentukkipas, panjang 5-7 cm, berwarna kuning dengannoda ungu pada pangkal, bagian dalam oranyedan akhirnya berubah menjadi kemerah-merahan (Syamsuhidayat and Hutapea, 1991).
Daun waru mengandung senyawa fitokimiaberupa polifenol, saponin, flavonoid, serta me-ngandung alkaloida, asam amino, karbohidrat,asam organik, asam lemak, sesquiterpen dansesquiterpen quinon, steroid, triterpen.Sedangkan akar waru disamping mengandungsenyawa saponin, juga mengandung tanin danflavonoid (Kumar et al., 2008), sehingga dengandemikian tanaman waru dapat digunakan untuk
67
mengobati TBC, paru-paru, batuk, sesak napas,radang amandel (tonsillitis), demam, diareberdarah/berlendir, disentri pada anak, muntahdarah, radang usus, bisul, abses, mengatasirambut rontok dan cacingan (Indah dan Darwati,2013).
Jenis dan Organ Predileksi Cacing yangMenginfeksi Kambing Peranakan Ettawah(PE)
Dari hasil pemeriksaan feses segar seba-nyak 20 sampel di Laboratorium Parasit BalaiBesar Veteriner Denpasar ditemukan beragamjenis cacing diantaranya cacing Strongylus sp,Strongyloides sp ., Haemonchus sp.,Bonustomum sp. dan Trichostrongilus sp. Hal inisesuai dengan temuan lain tentang prevelensiparasit gastrointestinal pada kambing dandomba yang ditemukan di Kenya (Pfukenyi et al.,2007). Sementara nematoda saluran pencernaanyang ditemukan pada ternak kambing dan dombadi Indonesia diantaranya Haemonchuscontortus,Trichostrongylus sp., dan Bonustomumsp (Adiwinata dan Sukarsih, 1992). Cacing yangmenginfeksi kambing PE ditemukan pada organtarget seperti terlihat Tabel 1. Infeksi cacingterjadi secara tunggal maupun majemuk (infeksilebih dari satu jenis cacing), dimana infeksimajemuk/gabungan terjadi sebanyak 60%.Infeksi tunggal diakibatkan cacing Haemonchussp. sebesar 20%, infeksi gabungan oleh cacingStrongylus sp. dan Trichostrongylus sp. sebesar20,5% serta infeksi gabungan oleh cacingStrongylus sp., Strongyloides sp. danBonustomum sp.sebesar 20 %.
Infeksi parasit cacing pada saluranpencernaan ternak kambing umumnyaberlangsung secara heterogen yaitu denganbermacam-macam parasit. Penyakit ini seringdiistilahkan dengan poliparasitisme dimanaterdapat lebih dari satu cacing yang menyerangsatu individu. Pada kebanyakan infeksi alamiah
akan terdapat lebih dari satu genus atau spesiesyang menyerang seekor ternak (Anonim, 2003).Siregar (2008) melaporkan bahwa infeksi alamipada hewan terjadi lewat kontaminasi makananyang tercemar oleh larva infektif sedikitdemisedikit setiap hari selama satu periode yangpanjang.
Dari beberapa penelitian melaporkandimana prevelensi infestasi campuran olehbeberapa jenis cacing cukup tinggi dapatmencapai 90% (Dessalegn,1999). Tingginyatingkat investasi campuran terjadi diduga sebagaiakibat kurang efisiennya metode kontrolkesehatan terhadap ternak yang diterapkan.Secara umum peternak jarang mengambiltindakan khusus misalnya memisahkan hewansakit dari kelompoknya, memberikan vitamin,memberikan pengobatan sesuai dengan gejalayang terlihat malah justru ternak yang sakitdibiarkan tetap bergabung dengan kelompoknya.
Tingkat Sebaran Cacing yang MenginfeksiKambing Peranakan Ettawah (PE)
Kambing PE terpelihara dalam kandangpanggung, berlantai semen serta bercelah.Kambing terlihat kurang bagus, dimana bulusekitar pantat kotor, kurus dan banyak feses cairserta lembek menempel pada bulu sekitar bawahanus serta berserakan dilantai kandang. Gejalaklinis Nampak seperti mencret. Ternak biasanyahanya menunjukkan gejala subklinis yang tidakbegitu diperhatikan oleh peternak, hal ini bisamenimbulkan gejala hingga ketahap yang lebihkronis, seiring dengan kurangnya nutrisi yangdiberikan ke ternak dan tingkat stres yangmeningkat, membuat parasit berproliferasi cukupbaik sehingga siklus hidupnya berlangsungsecara optimal (Mulatu et al., 2012).
Pada Tabel 2 terlihat dimana tingkat kejadianinvestasi cacing saluran pencernaan ditiapperlakuan pada kambing yang dipelihara dalamkandang model panggung secara keseluruhan
Tabel 1. Jenis dan organ predileksi cacing yang menginfeksi kambing PE
Jenis cacing Predileksi Total ( EPG)
Haemonchus sp. Rumen (abomasum) 100Strongylus sp., Trichostrongylus sp. Rumen dan Retikulum 260Trichostrongylus sp., Paramphistomum sp., Lambung dan Rumen 180Strongyloides sp. dan RetikulumBonustomum sp. Rumen 110
Tingkat Efektitivitas Ekstrak Daun Waru (Hibiscus tiliaceus) terhadap Parasit GastrointestinalPada Saluran Pencernaan Kambing Peranakan Ettawah ..... | I Wayan Sudarma, dkk.
68 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
terjadi sebesar 65%. Hasil ini mengindikasikanbahwa hasil yang diperoleh masih dibawah hasilpenelitian Donald (2003) yang menyatakanprevelensi cacing Haemonchus contortus padakambing dan domba di Ethiopia sebesar 98,8%.Namun hasil penelitian ini lebih tinggidibandingkan dengan hasil penelitian yangdilaporkan oleh Mukti et al. (2014) dimanaprevelensi cacing nematoda pada saluranpencernaan kambing PE sebesar 51,9%, dan51,4%. Hal ini terjadi akibat kurangnyapengetahuan yang dimiliki oleh para peternakdalam menangani kontrol kesehatan dalaminterval pemberian dan ketepatan dosis obatcacing sehingga dapat berdampak terhadapresisten terhadap obat, dan bila pemberiannyadilakukan secara berulang maka dapatmenimbulkan galur cacing yang resisten(Katzung, 2004).
Jumlah Telur Cacing yang MenginfeksiKambing Peranakan Ettawah (PE)
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkandimana ekstrak daun waru pada level 50 cc/ekor/hari mampu memberikan efek antelmintikyang
terbaik dibanding kontrol dan level 25 cc/ekor/hari walau tidak memberi respon nyata padapenggunaan pada level 75 cc/ekor/hari, dimanaefektivitas daun waru mulai terlihat pada mingguke II semenjak perlakuan, jelas terlihat padasemua perlakuan bila di banding perlakuankontrol, dimana perlakuan yang tanpa pemberianekstrak daun waru terlihat terjadi peningkatanjumlah butir telur cacing pada tiap gram fesessampel namun sebaliknya pada taraf perlakuanterlihat terjadi penurunan jumlah telur cacing.Halini sejalan pernyataan Beriajaya et al.,(2006)bahwa waktu inkubasi telur cacing untukmenghitung telur cacing yang menetas dapatdilakukan setelah 48 jam pada suhu kamar.Melalui uji in vitro terhadap telur cacingmerupakan persentase telur cacing yangmenetas selama 48 jam. Hal ini terjadi dimanatelur cacing dapat bertahan hingga 48 jam di suhuruang dalam keadaan baik. Pemilihan waktupengamatan pada jam ke-24 dapat mempercepatwaktu dan mendapatkan hasil yang optimalkarena dalam keadaan normal kondisi telur padajam ke-24 masih baik (Ekawasti et al. 2017).Dengan menurunnya jumlah telur cacing dalamfeses ternak dalam kurun waktu lebih dari 48 jam
Tabel 2. Tingkat prevalensi cacing pada saluran pencernaan kambing PE jantan
Perlakuan Jumlah sampel Jumlah sampel terinvestasi Persentase investasi (%)
P0 5 4 65P1 5 4 65P2 5 4 65P3 5 4 65
Tabel 3.Jumlah telur cacing yang menginfeksi sebelum dan sesudah perlakuan terhadap kambing PE.
69
menandakan senyawa fitokimia berupa tanin,saponin, flavonoid dari ekstrak daun warutelah mulai bekerja ditiap perlakuan walaukerjanya belum optimal,seperti terlihat padatabel 3.
Untuk mengetahui tingkat efektifitas dayalarvacidal maupun daya ovicidal dari suatutanaman obat dapat dilihat dari jumlah total EPGbutir telur dalam feses ternak, dimana dari tabeldiatas menunjukkan tingkat efektivitas dariekstrak daun waru pada level 50 cc/ekor dapatmenyebabkan terjadinya penurunan dayaovicidal telur cacing sebesar 35% serta dayalarvancidalnya hingga32%, sedangkanpenggunaan ekstrak daun waru pada level 25cc/gram/ekor dan 75 cc gram/ekor memiliki dayaovicidal telur cacing masih berada dibawahnyayakni masing-masing sebesar 27% dan 30%serta daya larvacidal masing-masing sebesar28% dan 30%.Hal ini sesuai dengan pernyataanMolan et, al., (2000) dimana senyawa fitiokimiadari tanaman obat dapat mengurangi jumlah telurcacing menetas hingga 34%-36 % danmenurunkan daya motilitas larva hingga 32%-35% sehingga tingkat perkembangan telur cacingmengalami penurunan.
Kemampuan daya antelmintik larvacidal dariekstrak daun waru berkaitan erat dengankandungan senyawa fitokimia, salah satunyaberupa senyawa tanin yang mampumenghambat kerja enzim,serta mampu merusakmembran cacing (Shahidi & Naczk,1995).Terlihat dimana dengan terhambatnyakerja enzim dapat menyebabkan prosesmetabolisme pencernaan cacing menjaditerganggu sehingga cacing akan kekurangannutrisi sari makanan yang pada akhirnya cacingakan mengalami kematian akibat kekurangantenaga. Membran cacing yang rusak akibatsenyawa tanin menyebabkan cacing mengalamiparalisis yang akhirnya mati. Tanin umumnyaberasal dari senyawa polifenol yangmemilikikemampuan untuk mengendapkan protein dalamtubuh cacing dengan membentuk koopolimeryang tidak larut dalam air (Tiwow et al., 2013).Disamping itu pula senyawa fitokimia berupasaponin dalam daun waru dapat mengikatmolekul sterol yang ada pada permukaanmembran sel cacing (Hassan et al., 2008), sertasaponin dapat menurunkan viabilitas sel cacingdengan cara merubah permeabilitas membransel organisme (Patra et al., 2006). Ekstrak airdaun waru (Hibicus Tiliaceus) diketahui
mengandung beberapa senyawa yang memilikiaktivitas antioksidan (Chinta et al.,2010)diantaranya berupa vitamin C, vitamin E,vitamin A, vitamin K, saponin, flavonoid, alkaloida,asam amino, karbohidrat, asam organik, asamlemak, sesquiterpen dan sesquiterpen quinon,steroid, triterpene (Syamsuhidayat and Hutapea,1991). Mekanisme penghambatan parasit akibatekstrak daun waru berasal dari kandunganantioksidan yang merupakan jenis obatantiparasit yang terus dikembangkan.Antioksidan diketahui juga dapat menyebabkanpeningkatan stres oksidatif atau mengganggumekanisme parasit cacing untuk melindungi diridari oksidan sehingga dapat menurunkanviabilitas parasit cacing.
Turunnya jumlah telur cacing pada levelpenggunaan ekstrak daun waru akibat senyawatanin yang terkandung dalam daun waru yangmemiliki aktivitas ovacidal dapat mengikat telurcacing pada lapisan luarnya yang terdiri atasprotein sehingga pembelahan sel didalam telurcacing tidak dapat berlangsung, pada akhirnyalarva tidak terbentuk, membunuh dan memutusdaur hidup cacing dewasa, larva maupun telurcacing (Tiwow et al., 2013).
Senyawa tanin dalam ekstrak daun waruselain memiliki aktivitas ovicidal juga mampumembunuh larva cacing, dimana senyawa tanindapat mengikat serta mengendapkan proteinyang terdapat pada lapisan outer membrane telurcacing, membentuk koopolimer yang larut dalamair. Senyawa tanin dapat mengganggupembelahan sel dalam telur hingga stadium larvacacing tidak terbentuk, menyebabkan telurcacing gagal menetas. Disamping itu mekanismepenghambatan tanin dengan cara melisiskandinding sel cacing selain akibat senyawa saponindan flavonoid, sehingga memudahkan senyawatanin masuk ke dalam dinding sel cacing (Rastogietal., 2009).
Senyawa flavonoid dari ekstrak daun warumemiliki ciri berbau tajam, berpigmen yang dapatlarut dalam air. Flavonoid memiliki peranansebagai antiparasit (Rastogi et, al., 2009).Dinding cacing yang terkena flavonoid dapatmenyebabkan kehilangan permeabilitas sel,selain itu flavonoid merupakan senyawa fenoldimana senyawa ini dapat merusak permeabilitascacing dan merusak dinding telur cacing(Harbone, 1987).
Lebih lanjut Molan et al., (2000) menyatakanbahwa senyawa fitokimia berupa tanin dari
Tingkat Efektitivitas Ekstrak Daun Waru (Hibiscus tiliaceus) terhadap Parasit GastrointestinalPada Saluran Pencernaan Kambing Peranakan Ettawah ..... | I Wayan Sudarma, dkk.
70 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
tanaman obat dapat mengurangi perkembanganlarva cacing nematoda hingga 91%.Ditinjau dariderajat tingkat infeksi, infeksi yang terjadi masihtergolong sedang yakni sebesar 650 butir/gramfeses. Menurut Levine (1990) pada infeksi ringanakan ditemukan telur cacing 1-499 butir/gramfesespada infeksi sedang akan ditemukan jumlahtelur cacing 500-5000 butir/gram feses.
Analisa Ekonomi Pemakaian Biaya EkstrakDaun Waru Sebagai Obat Cacing padaKambing Peranakan Ettawah (PE)
Dalam penanggulangan penyakit parasitcacing atau penyakit saluran pencernaangastrointestinal pada ternak kambing, sebagaipilihan alternatif dapat digunakan denganpemanfaatan tanaman waru secara tradisional.Berikut perbandingan pengeluaran biayapenangan penyakit cacingan dalam levelpenggunaan dosis yang berbeda-beda sepertipada tabel 4.
Tabel 4. Perbandingan biaya yang dikeluarkan padatiap perlakuan
Dosis level pemakaian Biaya (Rp/ekor)(ekor/hari)
25 cc 2.45050 cc 4.90075 cc 7.340
Dari tabel 4 menunjukkan bahwa pemberianekstrak daun warupada level 25 cc/ekor/haridalam sehari sekali pemberian terhadap1 ekorkambing memerlukan biaya masing-masingsebesar Rp 2.450, pada level 50 cc/ekor/haridalam sehari sekali pemberian terhadap 1 ekorkambing memerlukan biaya masing-masingsebesar Rp.4.900,sedangkan pada level 75 cc/ekor/hari dalam sehari sekali pemberianterhadap 1 ekor kambing memerlukan biayamasing-masing sebesar Rp 7.340. Berdasarkankajian ini menunjukkan bahwa pengobatandengan menggunakan obat cacing dari ekstrakdaun waru ditinjau dari segi harga tidak begitumahal, cukup efektif dan lebih mudah didapat danpengerjaannya cukup mudah.
KESIMPULAN DAN SARAN
Prevelensi parasit gastrointestinal terhadapkambing Peranakan Ettawah (PE) dalamkandang panggung daerah dataran tinggi diKelompok Tani”Menaka Giri” di Desa Sidemen,terinfeksi tunggal oleh cacing Haemonchus sp.(20%), infeksi gabungan oleh cacing Strongylussp. dan Trichostrongylus sp. (20,5%) dangabungan cacing Strongylus sp., Strongyloidessp. dan Paramphistomum sp.(20%).Dengantingkat sebaran cacing terjadi sebesar65%sertaderajat infeksi masihdalam stadiumsedang yakni 650 butir/gramfeses.Penggunaanekstrak daun waru pada level 50 cc/ekor/harimampu menurunkan jumlah larva sebesar 32%dan telur cacing sebesar 35%,sedangkan padalevel 25 cc/ekor/hari dan 75 cc/ekor/hari mampumenurunkan jumlah larva masing-masingsebesar 27% dan 30% dan telur cacing masing-masing sebesar 28% dan 30 %. Pemberianekstrak daun waru pada level 50 cc/ ekor/harisangat efektif dalam pengendalian maupunpengobatan penyakit cacingan pada ternakkambing.Pemakaian ekstrak daun waru sebagaiobat cacing pada kambing dapat dibuat denganmudah,tersedia sepanjang waktu dan mudahdidapat. Perlu penelitian lebih lanjut untukmengetahui tingkat prevelensi gastrointestinalpada kambing yang dipelihara di daerah dataranrendah.
KONTRIBUSI PENULIS
Penulis 1 dan 2 merupakan kontributorutama dalam penulisan artikel ilmiah ini.
DAFTAR PUSTAKA
Adiwinata, G., dan Sukarsih. 1992. GambaranDarah Domba yang Terinfeksi CacingNematoda Saluran Pencernaan SecaraAlami di Kabupaten Bogor. Penyakit Hewan.24(43): 13-16.
Anonim 2003.Pengendalian Penyakit Pada Sapi.Http:// primatani litbang.co.id diakses padatanggal 27 September 2007.
71
Anon. 2007. Daur Hidup Cacing haemonchus.http: // www. Sumber hewan.com /id/penyakitcacing. Diaskes tanggal 15September 2010.
Backer, TC.A. and R.C. Bakhuizen Van DenBrink, 1968, Flora of Java I, III, Wolters-Noordhoff N. V. Groningen,The Netherlans
Beriajaya, J. Manurung, dan D. Haryuningtyas.2006. Efikasi Cairan Serbuk Kulit BuahNanas untuk Pengendalian CacingHaemonchus contortus pada Domba.Seminar Nasional Teknologi Peternakan danVeteriner. 934 – 940.
BPS Karangasem, (2019).LuasWilayah MenurutJenis Penggunaan Tanah 2019.
Colin, J. 1999. Parasites dan Parasitic Deseaseof Domestic Animales.University ofPensylvania. June.28.
Chinta GC, Mullinti V, Prashanthi K, Sujata D,Pushpa KB, Ranganayakulu D. 2010. Anti-oxidant activity of the aqueous extract of theMorinda citrifolia leaves in triton WR-1339induced hyperlipidemic rats. Drug Invent.Tod. 2: 1-4
Dessalegn, L., 1999. The Epidemiology ofStrongyle infections in small ruminants underwarm tropical climate. J. Vet. Res., 71(3):219-226. Proceedings of the 13thAnnualConference of Ethiopian VeterinaryAssociation. Addis Ababa, Ethiopia
Donald, A.K. 2003. Epidemiology and SeasonalDynamics of Gastrointestinal Helminthosesof Small Ruminant in Easthern and SouthernSemi Aridzones of Ethiopia. http://wwwl.vetmed.fuberlin.de/ip-4donald.html
Ekawasti F, Suhardono Sawitri DH, Dewi DA,Wardhana AH, Martindah E. 2017. Mediapenyimpanan telur, larva dan cacingnematode sebagai media uji in vitro. Dalam:Puastuti W, Muharsini S, Inounu I,Tiesnamurti B, Kusumaningtyas E, Wina E,Herawati T, Hartati, Hutasoit R, penyunting.Prosiding Seminar Nasional TeknologiPeternakan dan Veteriner. Bogor(Indonesia): Pusat Penelitian danPengembangan Peternakan. hlm. 695-703.doi: 10.14334/Pros.Semnas.TPV-2017-p.695-703.
Harbone J B, 1987. Metode Fitokimia. Bandung:ITB Press.
Hassan SM, El-Gayar AK, Cadwell DJ, Bailey CA,Cartwright AL. 2008. Guar meal amelioratesEimeria tenella infection in broiler chicks. Vet.Parasitol. 157: 133-138.
Indah S.Y. dan Darwati, 2013, Keajaiban DaunTumpas Tuntas Penyakit Kanker, Diabetes,Ginjal, Hepatitis, Kolesterol, Jantung,GrahaPustaka, Jakarta, h. 60
Kamaraj, C., A.A. Rahuman, G. Elango, A.Bagavan, and A.A. Zahir. 2011. Anthelminticactivity of botanical extracts against sheepgastrointestinal nematodes, Haemonchuscontortus.Parasitol Res.109:37-45.
Katzung BG. 2004. Farmakologi dasar dan Klinik.Salemba Empat . Jakarta. Hal: 259, 286-287.
Kumar, S., Kumar, D., and Prakash, O., 2008,Evaluation of Antioxidant Potential, Phenolicand Flavanoid Contents of Hibiscus tiliaceusFlowers, ElectronicJournal of Environmental,Agriculturaland food Chemistry, 7 (4): 2863-2871
Levine,N.D.,1990.Parasitology Veteriner.Diterjemahkan oleh G. Asadhi. GadjahMada. University PressYogyakarta
Molan, A. L., G. C. Waghorn, B. R. Min,and W. C.McNabb. 2000. The effect of condensedtanin from seven herbages onTrichostrongylus colubriformis larvalmigration in vitro. FoliaParasitol. 47:39–44
Mukti, T., I.B.M. Oka, dan I.M. Dwinata. 2014.Prevalensi Cacing Nematoda SaluranPencernaan pada Kambiing PeranakanEttawa di Kecamatan Siliragung, KabupatenBanyuwangi, Jawa Timur. IndonesiaMedicus Veteriner. 5(4): 330-336.
Mulatu, M., T. Fentahun and B. Bogale. 2012.Gastrointestinal Helminthes Parasites inSheep: Prevalence and Associated RiskFactors, in and Around Gondar Town,Northwest Ethiopia. Advan. Biol. Res. 6 (5):191-195.
Nala, N., 1993, Usada Bali, PT. Upada Sastra,Denpasar
Patra AK, Kamra DN, Agarwal N. 2006. Effect ofplant extracts on in vitro methanogenesis,
Tingkat Efektitivitas Ekstrak Daun Waru (Hibiscus tiliaceus) terhadap Parasit GastrointestinalPada Saluran Pencernaan Kambing Peranakan Ettawah ..... | I Wayan Sudarma, dkk.
72 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
enzyme activities and fermentation of feedin rumen liquor of buffalo. Anim. Feed Sci.Technol. 128: 276-291.
Pfukenyi, M.D, S. Mukaratirwa, A.L. Willingham,dan J. Monrad. 2007. Epidemiologicalstudies of parasitic gastrointestinalnematodes, cestodes, and coccidiainfections in cattle in the highveld andlowveld communal grazing areas ofZimbabwe. Journal of Veterinary Research.74: 129-142.
Rastogi T, Bhutda V, Moon K, Aswar PB, andKhadabadi SS. 2009. Comparative Studieson Anthelmintic Activity of Moringa oleiferaand Vitex Negundo. Asian J. ResearchChem. 2(2): April-June, 2009:181-182.
Shahidi, F and M. Naczk. 1995. FoodPhenolics.Technomic Inc, Basel.
Siregar, S.B.2008. Penggemukan Sapi.EdisiRevisi. Penebar Swadaya. Depok
Syamsuhidayat, S. and Hutapea, J. (1991)Inventaris Tanaman Obat Indonesia I.
Steel, R. G. D. and J. H. Torrie. 1990. Prinsip danProsedur Statistik. Suatu PendekatanBiometrik. Alih Bahasa Ir.B. Soemantri. EdII. Gramedia Jakarta
Sutama, I.K dan I.G.M. Budiarsana. 2009.Panduan Lengkap Beternak Kambing danDomba. Penebar Swadaya, Jakarta
Tiwow, D., Widdhi, B dan Novel, S.K. 2013. Ujiefek antelmintik ekstrak etanolbiji pinang(Areca catechu) terhadap cacing Ascarislumbricoides danAscaridia galli secara invitro. Pharmacon 2 (02): 76-80
73
TINGKAT SERANGAN HAMA UTAMA DAN HASIL PANENBEBERAPA VARIETAS JAGUNG DI LINGKUNGAN SAWAH TADAH HUJAN
Ni Made Delly Resiani1 dan I Nengah Duwijana2
1)Peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali2)Penyuluh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, DenpasarE-mail: [email protected]
Submitted date : 22 Januari 2021 Approved date : 26 Pebruari 2021
ABSTRACT
The Level of Main Pest Attack and Harvest of Some Variety of Cornin the Rainfed Land Environment
Rainfed land are one of the land resources that have great potential for the development of agriculturaldevelopment. Various attempts have been made by the government to achieve this condition. One of them isthe development of new superior maize varieties. The research was conducted in Subak Aseman IV, TanguntitiVillage-East Selemadeg District, Tabanan Regency. Aim to analyze the level of attack by major pests andyields of maize. Research time April - August 2019. Using a randomized block design with 3 treatments of cornvarieties (J), namely Bima 20 URI (J1); Nasa 29 (J2) and NK 228 (J3). Each treatment was repeated 10 times.The data analysis used diversity analysis, followed by the LSD 5% test for the observed parameters. Theresults showed that the highest level of attack, armyworms and cob borer was shown in the Bima 20 URItreatment (7.65%) which was not significantly different from Nasa 29 (6.22%). Stem borer attack has no significanteffect on the three test treatments. The highest plant height was shown in the treatment of NK 228 (270.00).The highest stover weight above ground was shown in the treatment of NK 228 (18.60) and the lowest was inthe treatment of Bima 20 URI (12.23). The ear weight with the highest weight was shown in the treatment of NK228 (286.49), followed by Nasa 29 (256.84) and Bima 20 URI (214.15). The highest weight of the cob withouthusk, the weight of the harvested dry seed, and the highest total weight of the plant above ground were shownin the treatment of NK 228 (251.17; 197.03 and 636.8). The highest harvest index was shown in the Bima 20URI treatment which was not significantly different from Nasa 29 (1.17 and 1.13). The highest weight of storeddry shelled seeds was shown in treatment NK 228 (134.77). It was concluded that NK 228 showed the besttreatment among the three varieties with the lowest level of main pest attack and the highest yield of dry shelledstored weight.
Keywords: Main pests, maize, rainfed land
ABSTRAK
Sawah tadah hujan adalah salah satu sumber daya lahan yang mempunyai potensi besar untukpengembangan pembangunan pertanian. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah guna mewujudkan kondisitersebut. Salah satunya adalah pengembangan varietas jagung unggul baru. Penelitian dilaksanakan di SubakAseman IV, Desa Tanguntiti-Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan. Bertujuan untuk menganalisistingkat serangan hama utama dan hasil panen jagung. Waktu penelitian April - Agustus 2019. Menggunakanrancangan acak kelompok dengan 3 perlakuan varietas jagung (J) yakni varietas jagung Bima 20 URI (J1);Nasa 29 (J2) dan NK 228 (J3). Setiap perlakuan diulang 10 kali. Analisis data menggunakan analisis keragaman,dilanjutkan dengan uji BNT 5% untuk parameter teramati. Hasil penelitian menunjukkan tingkat serangan, ulatgrayak dan penggerek tongkol tertinggi ditunjukkan pada perlakuan Bima 20 URI (7,65%) yang tidak berbedanyata dengan Nasa 29 (6,22%). Serangan penggerek batang berpengaruh tidak nyata pada ketiga perlakuanuji. Tinggi tanaman tertinggi ditunjukkan pada perlakuan NK 228 (270,00). Bobot brangkasan atas tanahtertinggi ditunjukkan pada perlakuan NK 228 (18,60) dan terendah pada perlakuan Bima 20 URI (12,23). Bobot
Tingkat Serangan Hama Utama dan Hasil Panen Beberapa Varietas JagungDi Lingkungan Sawah Tadah Hujan | Ni Made Delly Resiani, dkk.
74 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
tongkol dengan kelobot tertinggi ditunjukkan pada perlakuan NK 228 (286,49), diikuti Nasa 29 (256,84) danBima 20 URI (214,15 ). Bobot tongkol tanpa kelobot, bobot biji pipilan kering panen, dan bobot total tanaman diatas tanah tertinggi masing-masing ditunjukkan pada perlakuan NK 228 (251,17;197,03 dan 636,8). Indekspanen tertinggi ditunjukkan pada perlakuan Bima 20 URI yang tidak berbeda nyata dengan Nasa 29 (1,17 dan1,13). Bobot biji pipilan kering simpan tertinggi ditunjukkan pada perlakuan NK 228 (134,77). DisimpulkanJagung NK 228 menunjukkan perlakuan terbaik diantara ketiga varietas tersebut dengan tingkat seranganhama utama terendah serta hasil bobot pipilan kering simpan tertinggi.
Kata kunci: Hama utama, jagung, sawah tadah hujan
PENDAHULUAN
Jagung merupakan salah satu komoditasstrategis nasional karena merupakan makananpokok kedua setelah padi (Wahyudin et al., 2016;Syamsia, 2019). Menurut Iriany et al. (2010)jagung berasal dari Amerika Tengah dan daridaerah ini jagung tersebar dan ditanam diseluruhdunia. Jagung mulai berkembang di AsiaTenggara pada pertengahan tahun1500an danpada awal tahun 1600an, yang berkembangmenjadi tanaman yang banyak dibudidayakan diIndonesia,Filipina, dan Thailand.Jagungmengandung protein yang penting dalam menumasyarakat di Indonesia selain sebagai sumberkarbohidrat. Suarni dan Yasin (2011).mengatakan bahwa jagung kaya akan komponenpangan fungsional, termasuk serat pangan yangdibutuhkan tubuh, asam lemak esensial,isoflavon, mineral (Ca, Mg, K, Na, P, Ca dan Fe),antosianin, betakaroten (provitamin A), komposisiasam amino esensial, dan lainnya. Selainsebagai bahan pangan, jagung juga merupakansumber utama energi bahan pakan.
Permintaan akan jagung terus meningkatdari tahun ke tahun, sementara produksi belummampu mecukupi kebutuhan nasional sehinggaharus impor. Produktivitas jagung di tingkat petanimasih rendah, baru mencapai 4,8 t/ha,sedangkan di tingkat penelitian dapat mencapai6,0–10 t/ha, bergantung pada kondisi lahan danteknologi yang diterapkan (Aqil et al., 2014;Sutoro, 2015; Manuel et al., 2018).
Upaya peningkatan produksi jagung dapatdilakukan dengan cara penterapan teknologibudidaya (Abdurrahman et al., 2013).. Beberapaupaya yang telah dilakukan diantaranyamemperluas areal tanam (ekstensifikasi) danintensifikasi (Maruapey dan Faesal, 2010).Pesireron dan Senewe (2011); Yukarie et al.(2016) menyatakan bahwa dalam peningkatanproduksi jagung diperlukan pemahaman untukmengelolanya agar bersinergis sehinggadiperoleh hasil yang tinggi . Margaretha dan
Syuryawati (2017);Yati dan Anna (2016) danSyuryawati dan Faesal (2016) menyatakanbahwa memadukan sejumlah komponenteknologi sesuai dengan kondisi lingkungantumbuh tanaman diharapkan dapatmeningkatkan produktivitas, efisiensi produksi,dan pendapatan usahatani jagung.
Upaya peningkatan produksi jagung melaluiperluasan areal tanam, dapat dikembangkan dilahan sawah tadah hujan (Eko et al., 2018).Misran (2013) menambahkan bahwa lahansawah tadah hujan atau lahan sawah semiintensif merupakan sumberdaya fisik yangpotensial untuk pengembangan komoditasjagung. Ditambahkan lagi pengembangan jagungdi lahan sawah tadah hujan sangat strategiskarena umumnya lahan tersebut tidakdimanfaatkan setelah padi musim tanam I dantidak cukup air untuk menanam padi musimtanam II, sehingga terdapat peluang menanamjagung karena kebutuhan airnya relatif lebihrendah dibandingkan dengan padi yang diairisampai tergenang. Namun demikian terdapatbeberapa kendala yang dihadapi petani dalampengembangan jagung di lahan sawah tadahhujan seperti cekaman air terutama kekeringan,kekurangan bahan organik tanah, dan seranganhama serta penyakit tanaman. Walker (1987)menyatakan bahwa telah diketahui sekitar 50spesies serangga yang menyerang tanamanjagung tetapi hanya beberapa di antaranya yangsering menimbulkan kerusakan yang berartiseperti ulat grayak, penggerek cabang dantongkol. Ulat grayak merupakan hama yangmenyerang bagian daun tanaman jagung. Hamatersebut bersifat polifag yakni selain menyerangtanaman jagung juga menyerang tanaman padi,sorgum, dan kacang-kacangan. Daun tanamandapat dimakan habis sampai hanya tersisa tulangdaunnya dan mati, terutama pada saat terjadinyapeledakan populasi. Ulat grayak dapatmenyerang seluruh stadia pertumbuhan tanamanjagung. Heliothis sp. terutama merusak tongkoljagung, sehingga kualitas jagung kalau dijual
75
muda jadi murah. Tongkol dapat rusak secarakeseluruhan kalau serangannya diikuti olehtumbuhnya cendawan yang menghasilkanmikotoksin. Heliothis sp. polifag yakni seranggaini juga menyerang tembakau, sorgum, kapas,kentang, tomat, dan kacang-kacangan. Larvayang baru menetas akan makan pada jambultongkol, dan kemudian membuat lubang masukke tongkol. Ketika larva makan, akan tertinggalkotoran dan tercipta iklim mikro yang cocok untukbertumbuhnya jamur yang menghasilkanmikotoksin sehingga tongkol rusak. Penggerekini juga dapat menyerang tanaman muda,terutama pada pucuk atau malai yang. dapatmengakibatkan tidak terbentuknya bunga jantan,berkurangnya hasil dan bahkan tanaman dapatmati.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulistertarik untuk melakukan penelitian jagung dilahan sawah tadah hujan dengan tujuan untukmenganalisis tingkat serangan hama dominanserta hasil panen pada beberapa varietas jagung.
METODOLOGI
Penelitian dilaksanakan di Subak AsemanIV, Desa Tanguntiti-Kecamatan Selemadeg TimurKabupaten Tabanan. Waktu penelitian April -Agustus 2019. Menggunakan rancangan acakkelompok sederhana dengan 3 perlakuanvarietas jagung (J) yakni varietas jagung Bima20 URI (J1); Nasa 29 (J2) dan NK 228 (J3).Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 10kali. Teknis pelaksanaan dilapang berpedomanpada Pedoman Umum Pengelolaan TerpaduJagung (Litbang, 2016), meliputi varietas unggulbaru, benih bermutu dan berlabel, jarak tanam80 cm x 40 cm (2 biji per lubang), Pemupukanberdasarkan kebutuhan tanaman dan status haratanah. Kebutuhan hara N tanaman diukur denganBagan Warna Daun (BWD) untuk mengetahuitingkat kehijauan daun jagung sedangkankebutuhan hara P dan K dengan Perangkat UjiTanah Kering (PUTK). Pupuk N diberikan duakali, yakni pada umur tanaman 7-10 hari setelahtanam (HST) dan 30-35 HST. BWD digunakanpada saat tanaman berumur 40-45 HST untukmendeteksi kecukupan N bagi tanaman.
Pengolahan lahan dilakukan dengan sistemtanpa olah tanah (TOT), Pembuatan salurandrainase dibuat pada saat penyiangan pertama.Pemberian bahan organik dengan pupuk sapi
terfermentasi 2 ton/Ha. Pembumbunan dengantujuan untuk memberikan lingkungan akar yanglebih baik, agar tanaman tumbuh kokoh dan tidakmudah rebah. Pembumbunan dilakukanbersamaan dengan penyiangan pertama secaramekanis. Pengendalian gulma dilakukan secaramekanis, pengendalian hama dan penyakitberdasarkan pendekatan pengendalian hamadan penyakit secara terpadu: Panen tepat waktudan pengeringan segera. Panen dilakukan jikakelobot tongkol telah mengering atau berwarnacoklat, biji telah mengeras, dan telah terbentuklapisan hitam minimal 50% pada setiap baris biji.tongkol yang sudah dipanen segera dijemur, ataudiangin-anginkan.
Parameter yang diamati meliputi tinggitanaman maksimum, bobot brangkasan atastanah, bobot tongkol dengan kelobot,bobottongkol tanpa kelobot, bobot biji pipilan keringpanen, bobot total tanaman di atas tanah, bobotpipilan kering simpan, indeks panen, bobot buahtanpa kelobot ubinan, tingkat serangan hamautama serta bobot pipilan kering simpan perhektar.
Tingkat serangan hama utama dihitungmenggunakan rumus:
jumlah tanaman terserangTingkat serangan (%) = X 100% jumlah tanaman yang diamati
Data dianalisis dengan analisis keragamansesuai dengan rancangan yang digunakan.Analisis lanjut akan dilakukan dengan uji BNT5% untuk parameter teramati (Gomez danGomez, 1995).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis statistika menunjukkanperlakuan uji berpengaruh nyata dan tidak nyataterhadap parameter yang diamati (Tabel 1 - 4).Tingkat serangan penggerek batangberpengaruh tidak nyata pada ketiga perlakuanuji, sementara ulat grayak dan penggerek tongkolberpengaruh nyata. Serangan ulat grayaktertinggi ditunjukkan pada perlakuan jagung Bima20 URI (7,65%) namun tidak berbeda nyatadengan jagung Nasa 29 (6,22%) dan seranganterendah ditunjukkan pada jagung NK 228(5,98%) atau 27,92% serangan dapat ditekanpada jagung NK 228 (Tabel 1.). Serangan
Tingkat Serangan Hama Utama dan Hasil Panen Beberapa Varietas JagungDi Lingkungan Sawah Tadah Hujan | Ni Made Delly Resiani, dkk.
76 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
penggerek tongkol tertinggi ditunjukkan padajagung Bima 20 URI (9,24%) diikuti jagung Nasa29 (7,62) yang tidak berbeda nyata denganjagung NK 228 (7,29%) (Tabel 1.).
Perlakuan uji berpengaruh nyata terhadapkomponen pertumbuhan dan hasil panen jagung.Tinggi tanaman jagung tertinggi ditunjukkan padaperlakuan jagung NK 228 (270,00 cm), di ikutiNasa 29 (252,95 cm) dan Bima 20 URI (219,45cm) atau dengan kata lain tinggi jagung NK 228,6,74 dan 23,99% lebih tinggi dibanding jagungNasa 29 dan Bima 20 URI (Tabel 2.). Bobotbrangkasan atas tanah tertinggi ditunjukkan padaperlakuan jagung NK 228 (18,60 g) dan terendahpada perlakuan Bima 20 URI (12,23 g) atau bobotbrangkasan atas tanah jagung NK 228 lebihtinggi 15,74% dibanding jagung Nasa 29 (16,07g)(Tabel 2.). Demikian juga dengan komponenbobot tongkol dengan kelobot, diperoleh hasilbobot tongkol dengan kelobot tertinggiditunjukkan pada perlakuan jagung NK 228(286,49 g), diikuti Nasa 29 (256,84) dan Bima20 URI (214,15 g) (Tabel 2).
Perlakuan uji berpengaruh nyata terhadapbobot tongkol tanpa kelobot, bobot biji pipilankering panen dan bobot total tanaman di atastanah (Tabel 3.). Bobot tongkol tanpa kelobottertinggi ditunjukkan pada perlakuan NK 228(251,17) diikuti Nasa 29 (236,01) dan Bima 20URI (187,22) atau dengan kata lain bobot tongkoltanpa kelobot NK 228, 34,16% dibandingkanBima 20 URI. Bobot biji pipilan kering panentertinggi ditunjukkan pada perlakuan NK 228(197,03) dan terendah pada Bima 20 URI(187,22) atau 27,98% lebih tinggi pada NK 228.Bobot total tanaman di atas tanah tertinggiditunjukkan pada perlakuan NK 228 (636,8),diikuti Nasa 29 (461,6) dan Bima 20 URI (366,91)atau 42,38% lebih tinggi pada NK 228 dibandingBima 20 URI (Tabel 3.).
Perlakuan uji berpengaruh nyata terhadaprerata bobot biji pipilan kering simpan baik pertanaman maupun per hektar dan indeks panen.Bobot biji pipilan kering simpan per tanamantertinggi ditunjukkan pada perakuan jagung NK228 (134,77) dan terendah pada Bima 20 URI
Tabel 1. Pengaruh perlakuan terhadap rerata tingkat serangan hama penggerek batang, ulat grayak danpenggerek tongkol
Perlakuan Penggerek batang (%) Ulat grayak (%) Penggerek tongkol (%) Nasa 29 4.17 a 6.22 a 7.62 bBima 20 URI 7.22 a 7.65 a 9.24 aNK 228 3.01 a 5.98 b 7.29 bKK (%) 22.52 20.59 BNT 5% 0.44 0.49
Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan tidaknyata pada taraf uji BNT 5% Data tingkat serangan hama utama dianalisis setelah ditransformasike dalam Arcsin” X%
Tabel 2. Pengaruh perlakuan terhadap rerata tinggi tanaman, bobot brangkasan atas tanah dan bobot tongkoldengan kelobot
Perlakuan tinggi tanaman (cm) bobot brangkasan bobot tongkolatas tanah (g) dengan kelobot (g)
Nasa 29 252.95 b 16.07 b 265.84 bBima 20 URI 219.45 c 12.23 c 214.15 cNK 228 270.00 a 18.60 a 286.49 aKK (%) 8.29 18.49 17.46 BNT 5% 6.10 0.86 13.25
Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan tidaknyata pada taraf uji BNT 5% Data bobot brangkasan atas tanah di analisis setelah di transformasike dalam bentuk (X+0,5)^0.5
77
(113,40) atau 12,98% lebih tinggi pada jagungNK 228. Indeks panen tertinggi ditunjukkan padaperlakuan jagung Nasa 29 (1,13) namun tidakberbeda nyata dengan Bima 20 URI (1,17) danterendah pada jagung NK 228 (0,95). Bobot bijipipilan kering simpan per hektar tertinggiditunjukkan pada perlakuan jagung NK 228 (8,42)dan terendah pada Bima 20 URI (7,09) yang tidakberbeda nyata dengan Nasa 29 (7,33) (Tabel 4.).
Tingkat serangan hama utama dan hasilpanen beberapa varietas jagung di lingkungansawah tadah hujan menunjukkan hasil nyata dantidak nyata. Tingkat serangan penggerek batangberpengaruh tidak nyata pada ketiga perlakuanuji, sementara ulat grayak dan penggerek tongkolberpengaruh nyata. Demikian juga terhadapkomponen hasil. Perlakuan uji berpengaruhnyata terhadap komponen pertumbuhan danhasil panen jagung. Tinggi tanaman, bobotbrangkasan atas tanah, bobot tongkol dengankelobot tertinggi ditunjukkan pada perlakuanjagung NK 228. Bobot tongkol tanpa kelobot,bobot biji pipilan kering panen dan bobot totaltanaman di atas tanah, tertinggi juga ditunjukkan
pada perlakuan NK 228. Perlakuan ujiberpengaruh nyata terhadap rerata bobot bijipipilan kering simpan baik per tanaman maupunper hektar dan indeks panen.
Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh sifatgenetik, faktor lingkungan, intensitas cahayamatahari dan suhu. Perbedaan sifat genetikmenyebabkan terjadinya perbedaan tanggapketiga varietas tersebut terhadap berbagaikondisi l ingkungan, sehingga aktivitaspertumbuhan yang ditunjukkan berbeda. JagungNK 228 merupakan jagung eksisting yang sudahlama di tanam petani di lokasi tersebut dan sudahberadaptasi baik di l ingkungan tersebut,sementara jagung Nasa 29 dan Bima 20 URImerupakan varietas yang baru pertama kali diuji coba. Kondisi ini sesuai dengan pendapatSadjad (1993) yang menyatakan bahwa,perbedaan daya tumbuh antar varietasditentukan oleh faktor genetiknya. Jumin (2005)menambahkan bahwa dalam menyesuaikan diri,tanaman akan mengalami perubahan fisiologisdan morfologis ke arah yang sesuai denganlingkungan barunya. Harjadi (1991) menyatakan
Tabel 3. Pengaruh perlakuan terhadap rerata bobot tongkol tanpa kelobot, bobot biji pipilan kering panen, danbobot total tanaman di atas tanah
Perlakuan bobot tongkol bobot biji pipilan bobot total tanamantanpa kelobot (g) kering panen (g) di atas tanah (g)
Nasa 29 236.01 b 194.13 a 461.6 bBima 20 URI 187.22 c 141.90 b 366.91 cNK 228 251.17 a 197.03 a 636.8 aKK (%) 20.10 15.76 20.86 BNT 5% 13.42 16.79 30.26
Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan tidaknyata pada taraf uji BNT 5%
Tabel 4. Pengaruh perlakuan terhadap rerata bobot biji pipilan kering simpan per tanaman, indeks panen, danbobot biji pipilan kering simpan (ton/ha)
Perlakuan bobot biji pipilan indeks panen Bobot biji pipilan keringkering simpan (g/tan) simpan (ton/ha)
Nasa 29 117.27 b 1.13 a 7,33 b Bima 20 URI 113.40 b 1.17 a 7,09 bNK 228 134.77 a 0.95 b 8,42 aKK (%) 15.19 13.04 15,1 BNT 5% 5.49 0.08 343,35
Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan tidaknyata pada taraf uji BNT 5%
Tingkat Serangan Hama Utama dan Hasil Panen Beberapa Varietas JagungDi Lingkungan Sawah Tadah Hujan | Ni Made Delly Resiani, dkk.
78 Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Vol 19 No. 1 April 2021
bahwa varietas tanaman yang berbedamenunjukkan pertumbuhan dan hasil yangberbeda walaupun ditanam pada kondisilingkungan yang sama. Adi et al. (2013)menyatakan bahwa perbedaan susunan genetikmerupakan salah satu faktor penyebabkeragaman penampilan tanaman. Genetik yangakan diekspresikan pada suatu fasepertumbuhan yang berbeda dapat diekspresikanpada berbagai sifat tanaman yang mencakupbentuk dan fungsi tanaman yang menghasilkankeragaman pertumbuhan tanaman.
Maruapey (2012) menyatakan bahwaperkembangan tanaman akan dipengaruhi olehlingkungan tumbuhnya terutama kelembabandan suhu di sekitar tanaman sangatmempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman.Setiap tanaman membutuhkan suhu optimaldalam kisaran tertentu sesuai dengan prinsifreaksi kimia, demikian juga dalam prosesmetabolisme. Penampilan pertumbuhantanaman jagung NK 228 pada peubah tinggitanaman menunjukkan perbedaan yang nyataantara perlakuan. Tinggi tanaman varietas jagungNK 228 tertinggi diantara ke perlakuan uji.Demikian juga terhadap komponen dan hasilpanen. Pesireron dan Senewe (2011)menyatakan bahwa genotipe yang berbeda akanmemberikan tanggapan yang berbeda meskipundi lingkungan yang sama. Dikatakan juga tinggitanaman merupakan salah satu parameter utamauntuk mengetahui tingkat adaptasi suatu varietaspada setiap agroekosistem yang berbeda.
Soehendi dan Syahri (2013) mengatakanbahwa tanaman yang tinggi mampu menerimaintensitas cahaya matahari secara penuh,sehingga proses fotosintesis dapat berlangsungoptimal sehingga meningkatkan suplai bahankering ke daun, batang dan biji yang memicupertumbuhan dan biomasa tanaman.Ditambahkan pula penampilan suatu karakterakan optimal jika tanaman tersebut berada padalingkungan yang sesuai, sebaliknya penampilantidak akan optimal jika berada pada lingkunganyang tidak sesuai. Penampilan suatu karakteryang heritabilitasnya tinggi memiliki pengaruhlingkungan sedikit sehingga penampilannya akanrelatif tetap, tetapi karakter yang heritabilitasnyarendah memiliki pengaruh lingkungan yang besarsehingga penampilannya mudah berubah.
KESIMPULAN
Varietas jagung NK 228 menunjukkanperlakuan terbaik dilingkungan sawah tadahhujan diantara ketiga varietas tersebut dengantingkat serangan hama utama terendah sertahasil bobot pipilan kering simpan tertinggi.Varietas jagung Nasa 29 dan Bima 20 URImerupakan varietas alternatif pilihan petanisebagai pengganti varietas eksisting.
UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih penulis sampaikan kepadaBadan Litbang Pertanian atas bantuan anggarandalam kegiatan ini, sehingga kegiatan dapatberjalan sebagaimana mestinya. Terima kasihjuga disampaikan kepada kepala Balai Besar danKepala BPTP Bali. Disampaikan juga ucapanterima kasih kepada teman-teman yang turutmembantu dalam pelaksanaan kegiatan inihingga terealisasinya tulisan ini. Semoga semuadiberikan kesehatan dalam menjalani kehidupanini.
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, P.,, Mbue, K.B., Hasmawi, H.2013. Respons Pertumbuhan Dan ProduksiBeberapa Varietas Tanaman JagungTerhadap Pemberian Pupuk N Dan K JurnalOnline Agroekoteknologi Vol.1, No.3.
Adi W.B. A. , Kuswanto, Andy Soegianto. 2013.Respon Lima Varietas Jagung (Zea Mays L.)Pada Aplikasi Pyraclostrobin. JurnalProduksi Tanaman. Volume 1 No.1
Aqil, M dan R.Y. Arvan. 2014. Deskripsi varietasunggul jagung. Maros: Balai PenelitianTanaman Serealia. 45p
Eko, I., St. Subaedah, A.Takdir. 2018. AnalisisKeragaan Genetik Jagung Toleran CekamanKekeringan Di Lahan Sawah TadahHujan.Jurnal Agrotek. Vol. 2 No. 2
Gomez, K.A dan A.A. Gomez. 1995. ProsedurStatistik Untuk Penelitian Pertanian .Diterjemahkan oleh: Endang Sjamsudin danJ.S Baharsjah. UI-Press. Jakarta
79
Harjadi, S. S. M. M. 1991. Pengantar Agronomi.PT Gramedia. Jakarta.
Iriany, R. N., M. Yasin H. G., Andi T. M., 2010.Asal, Sejarah, Evolusi, dan TaksonomiTanaman Jagung. Balai Penelitian TanamanSerealia, Maros.
Jumin, H. B. 2005. Dasar-Dasar Agronomi. EdisiRevisi. P. T. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Misran. 2013. Studi Komposit Potensi Jagungpada Lahan Sawah Tadah Hujan SetelahPertanaman Padi. Jurnal PenelitianPertanian Terapan Vol. 13 (2).
Maruapey, A. 2012. Pengaruh Dosis PemupukanKalium Terhadap Pertumbuhan DanProduksi Berbagai Asal Jagung Pulut (Zeamays ceratina. L). Jurnal Agroforestri, VII (1).
Maruapey, A. dan Faesal., 2010. PengaruhPemberian Pupuk KCl terhadapPertumbuhan dan Hasil Jagung Pulut (Zeamays ceratina. L). Prosiding Pekan SerealiaNasional 2010 ISBN :978-979-8940-29-3.p316-326.
Margaretha SL. dan Syuryawati. 2017. AdopsiTeknologi Produksi Jagung DenganPendekatan Pengelolaan Tanaman TerpaduPada Lahan Sawah Tadah Hujan. PenelitianPertanian Tanaman Pangan VOL. 1 NO. 1.
Manuel, P.X.,I. A.,Mayun,N.L.M. Pradnyawathi.2018. Pengaruh Kombinasi Jarak TanamDan Varietas Terhadap Pertumbuhan DanHasil Tanaman Jagung (Zea Mays L.) DiLoes, Sub District Maubara, District LiquisaRepupublica Democratica De Timor Leste .E-Jurnal Agroekoteknologi Tropika . Vol. 7,No. 2,
Pesireron dan Senewe. 2011. Keragaan 10Varietas/Galur Jagung Komposit Dan HibridaPada Agroekosistem Lahan Kering DiMaluku. Jurnal Budidaya Pertanian, 7 (2).
Litbang. 2016. PTT Jagung . DepartemenPertanian.Badan Penelitian danPengembangan Pertanian.
Sadjad, S. 1993. Kuantifikasi Metabolisme Benih.Gramedia, Jakarta.
Suarni dan Muh. Yasin. 2011. Jagung sebagaiSumber Pangan Fungsional. Iptek TanamanPangan .Vol. 6 No. 1.
Sutoro. 2015. Determinan agronomisproduktivitas jagung. IPTEK TanamanPangan 10(1):39-46.
Soehendi, R. dan Syahri. 2013. PotensiPengembangan Jagung di SumateraSelatan. Jurnal Lahan Suboptimal, 2 (1): 81-92.
Syuryawati dan Faesal. 2016. KelayakanFinansial Penerapan Teknologi Budi DayaJagung pada Lahan Sawah Tadah HujanPenelitian Pertanian Tanaman Pangan VOL.35 NO. 1
Syamsia Syamsia, Abubakar Idhan, . Kasifah.2019. Produksi Benih Jagung HibridaMenggunakan Sistem Tanam Tanpa OlahTanah (Tot). Jurnal Dinamika PengabdianVol 5 (1).
Walker, P.T. 1987. Measurement of insect pestpopulations and injury. In Crops LossAssessment and Pest Management Ed. P.S.Teng. The Americans PhytophatologySociety APS Press.
Wahyudin, A. ’” Ruminta ’” S. A. Nursaripah. 2016.Pertumbuhan dan hasil tanaman jagung(Zea mays L.) toleran herbisida akibatpemberian berbagai dosis herbisida kaliumglifosat Jurnal Kultivasi Vol. 15(2)
Yati, H. dan Anna, S. 2016. Pengujian AdaptasiBeberapa Varietas Jagung Hibrida SpesifikLokasi Di Kabupaten Majalengka. JurnalAgrotek Lestari Vol. 2, No. 1.
Yukarie A. W., Sularno, Junaidi. 2016. PengaruhVarietas Dan Sistem Budidaya TerhadapPertumbuhan, Produksi, Dan KandunganGizi Jagung (Zea Mays L.) Jurnal AgrosainsDan Teknologi, Vol. 1 No. 1.
Tingkat Serangan Hama Utama dan Hasil Panen Beberapa Varietas JagungDi Lingkungan Sawah Tadah Hujan | Ni Made Delly Resiani, dkk.
PEDOMAN BAGI PENULIS
BULETIN TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERTANIAN
1. Buletin Teknologi Pertanian memuat naskah ilmiah/semi ilmiah dalam bidang pertanian dalam arti luas.Naskah dapat berupa : hasil penelitian, pengkajian,artikel ulas balik (review). Naskah harus asli (belumpernah dipublikasikan) dan ditulis menggunakanbahasa indonesia.
2. Naskah diketik dengan kertas berukuran A4. Naskahdiketik dengan 1,15 menggunakan program olahkata MS Word, huruf Arial ukuran huruf 10.
3. Tata cara penulisan naskah hasil penelitianhendaknya disusun menurut urutan sebagai berikut: judul, identitas penulis, abstrak, abtract (bahasaInggris), pendahuluan, materi dan metode, hasil danpembahasan, kesimpulan dan saran, ucapan terimakasih, dan daftar pustaka. Gambar dan tableditempatkan pada akhir naskah, masing-masingpada lembar berbeda. Upayakan dicetak hitam\putih1,15 spasi, dan keseluruhan naskah tidak lebih dari10 halaman.3.1 Judul : Singkat dan jelas (tidak lebih dari 14
kata), ditulis dengan huruf besar.3.2 Identitas penulis : Nama ditulis lengkap (tidak
disingkat) tanpa gelar. bila penulis lebih dariseorang, dengan alamat instansi yangberbeda, maka dibelakang setiap nama diberiindeks angka (superscript). Alamat penulisditulis di bawah nama penulis, mencakuplaboratorium, lembaga, dan alamat indeksdengan nomor telpon/faksimili dan e-mail.Indeks tambahan diberikan pada penulis yangdapat diajak berkorespondensi (correspondingauthor).
3.3 Abstrak : Ditulis dalam bahasa indonesia danbahasa Inggris. Abstrak dilengkapi kata kunci(key words) yang diurut berdasarkankepentingannya. Abstrak memuat ringkasannaskah, mencakup seluruh tulisan tanpamencoba merinci setiap bagiannya. Hindarimenggunakan singkatan. Panjang abstrakmaksimal 250 kata.
3.4 Pendahuluan : Memuat tentang ruang lingkup,latar belakang tujuan dan manfaat penelitian.Bagian ini hendaknya membeikan latarbelakang agar pembaca memahami danmenilai hasil penelitian tanpa membacalaporan-laporan sebelumnya yang berkaitandengan topik. Manfaatkanlah pustaka yangdapat mendukung pembahasan.
3.5 Metode Penelitian : Hendaknya diuraikansecara rinci dan jelas mengenai bahan yangdigunakan dan cara kerja yang dilaksanakan,termasuk metode statiska. Cara kerja yangdisampaikan hendaknya memuat informasiyang memadai sehingga memungkinkanpenelitian tersebut dapat diulang denganberhasil.
3.6 Hasil dan Pembahasan : Disajikan secarabersama dan pembahasan dengan jelas hasil-hasil penelitian. Hasil penelitian dpat disajikandalam bentuk penggunaan grafik jika haltersebut dapat dijelaskan dalam naskah. Bataspemakain foto, sajikan foto yang jelasmenggambarkan hasil yang diperoleh. Gambardan table harus diberi nomor dan dikutip dalamnaskah. Foto dapat dikirim dengan ukuran 4 R.Biaya pemuatan foto bewarna akan dibebanike penulis. Grafik hasil pengolahan data dikirimdalam file yang terpisah naskah ilmiah dandisertai nama program dan data dasar
penyusunan grafik. Pembahasan yangdisajikan hendaknya memuat tafsir atas hasilyang diperoleh dan bahasan yang berkaitandengan laporan-laporan sebelumnya. Hindarimengulang pernyataan yang telahdisampaikan pada metode, hasil dan informasilain yang telah disajikan pada pendahuluan.
3.7 Kesimpulan dan Saran : Disajikan secaraterpisah dari hasil dan pembahasan.
3.8 Ucapan Terima Kasih : Dapat disajikan biladipandang perlu. Ditujukan kepada yangmendanai penelitian dan untuk memberikanpenghargaaan kepada lembaga mau punperseorangan yang telah membantu penelitianatau proses penulisan ilmiah.
3.9 Daftar Pustaka : disusun secara alfabetismenurut nama dan tahun terbit. Singkatanmajalah/jurnal berdasarkan tata cara yangdipakai oleh masing-masing jurnal.
Contoh penulisan daftar pustaka :
Jurnal/Majalah :Suharno. 2006. Kajian pertumbuhan dan produksi 8
varietas kedelai (Glysine max L) di lahan sawahtadah hujan. Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian. 2 (1) hlm.66 - 72
Buku :Houghton J. 1994. Global Warming. Lion Publishing plc,
Oxford, England.
Bab dalam buku :Carter, J.G., 1980. Environmental and biological controls
of bivalve shell mineralogy and microstructure. In:Rhoads, D.C. and Lutz, R.A. (Eds), Skeletal growthof aquatic organism. Plenum Press, New York andLondon: 93-134.
AbstrakWilcox GE, Chadwick BJ, Kertayadnya G. 1994.
Jembrana disease virus: a new bovine lentivirusproducing an acute severe clinical disease ini Bosjavanicus cattle. Abstrak 3rd Internastional Congresson Veterinary Virology, Switserland Sept. 4-7.
Prosiding KonferensiHerawati T., Suwalan S., Haryono dan Wahyuni, 2000.
Perananan wanita dalam usaha tani keluarga dilahan rawa pasang surut, Prosiding SeminarNasional Penelitian dan Pengembangan di LahanRawa. Cipayung, 25 – 27 Juli 2000, hlm 247 – 258.Puslitbangtan.
Tesis/DisertasiStone, I.G., 1963. A morphogenetic study of study stages
in the life-cycle of some Vitorian cryptograms. Ph.DThesis, Univ. of Melbourne.
Informasi di Internet:Badan Pusat Statistik. 2010. The results of population
census in 2010: The aggregate data per province.Jakarta, Agustus. http://www.bps. go.id/download_file/SP2010_agregat_data_ perProvinsi.pdf(Diakses: 29/8/2010).
4. Naskah dari artikel ulas balik (review), dan laporankasus sesuai dengan aturan yang lazim.
5. Pengiriman naskah buletin dapat diserahkankepada redaksi di Balai Pengkajian TeknologiPertanian (BPTP) Bali berupa hardfile dan softfile.