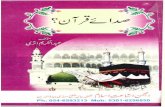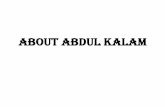ABDUL BAGAS ALKATIRI-FST.pdf
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of ABDUL BAGAS ALKATIRI-FST.pdf
PERILAKU MAKAN DAN STATUS GIZI
SIAMANG (Symphalangus syndactylus Raffles, 1821)
DI PUSAT PENYELAMATAN SATWA TEGAL ALUR, JAKARTA
ABDUL BAGAS ALKATIRI
PROGRAM STUDI BIOLOGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2020 M / 1442 H
i
Perilaku Makan dan Status Gizi Siamang (Symphalangus syndactylus
Raffles, 1821) di Pusat Penyelamatan Satwa Tegal Alur, Jakarta
SKRIPSI
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sains
pada Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ABDUL BAGAS ALKATIRI
NIM 11160950000033
PROGRAM STUDI BIOLOGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2020 M / 1442 H
ii
Perilaku Makan dan Status Gizi Siamang (Symphalangus syndactylus
Raffles, 1821) di Pusat Penyelamatan Satwa Tegal Alur, Jakarta
SKRIPSI
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sains
pada Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ABDUL BAGAS ALKATIRI
11160950000033
Menyetujui:
Pembimbing I, Pembimbing II,
Dr. Fahma Wijayanti, M.Si Narti Fitriana, M.Si
NIP.197006282014112002 NIDN. 0331107403
Mengetahui,
Ketua Program Studi Biologi
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Dr. Priyanti, M.Si
NIP. 197505262000122001
iii
PENGESAHAN UJIAN
Skripsi berjudul “Perilaku Makan dan Status Gizi Siamang (Symphalangus
syndactylus Raffles, 1821) di Pusat Penyelamatan Satwa Tegal Alur, Jakarta” yang
ditulis oleh Abdul Bagas Alkatiri, NIM 11160950000033 telah diuji dan dinyatakan
LULUS dalam sidang Munaqosyah Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 19 November 2020. Skripsi ini telah
diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Program Studi Biologi.
Menyetujui:
Penguji I, Penguji II,
Dr. Nani Radiastuti, M.Si Etyn Yunita, M.Si
NIP. 197505262000122001 NIP. 197006282014112002
Pembimbing I, Pembimbing II,
Dr. Fahma Wijayanti, M.Si Narti Fitriana, M.Si
NIP.197006282014112002 NIDN. 0331107403
Mengetahui,
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Ketua Program Studi Biologi,
Prof. Dr. Lily Surayya Eka Putri, M. Env., Stud. Dr. Priyanti, M. Si
NIP. 196904042005012005 NIP. 197505262000122001
iv
PERNYATAAN
DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR
HASIL KARYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIAJUKAN SEBAGAI
SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU
LEMBAGA MANAPUN.
Jakarta, 19 November 2020
Abdul Bagas Alkatiri
11160950000033
v
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum w.w.
Bismillahirrohmaanirrohiim, hamdan wa syukron lillah. Puji syukur penulis
panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat – Nya, sehingga pelaksanaan dan
penulisan laporan penelitian dengan judul “Perilaku Makan dan Status Gizi Siamang
(Symphalangus syndactylus Raffles, 1821) di Pusat Penyelamatan Satwa Tegal
Alur, Jakarta” dapat diselesaikan.
Penyusunan laporan penelitian dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan gelar sarjana Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan
Teknologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Penulis menyampaikan rasa
terima kasih kepada semua pihak yang atas segala bimbingan dan bantuan kepada
penulis selama ini dalam membuat dan menyusun laporan ini dan agar dapat bermanfaat
dan memberikan informasi yang berguna untuk semua pihak. Dalam penulisan laporan,
penulis ingin memberikan terima kasih kepada :
1. Prof. Dr. Lily Surayya Eka Putri, M. Env Stud. selaku Dekan Fakultas Sains dan
Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beserta jajarannya.
2. Dr. Priyanti, M. Si. selaku Ketua Program Studi Biologi Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta dan penguji II pada seminar proposal dan hasil yang
telah memberikan saran dan masukan yang membangun kepada Penulis.
3. Narti Fitriana, M. Si selaku Sekretaris Program Studi Biologi Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Pembimbing II yang senantiasa
membimbing dan memberi banyak ilmu, arahan dan bimbingan selama penelitian.
4. Dr. Fahma Wijayanti, M.Si selaku Pembimbing I yang senantiasa membimbing dan
memberi banyak ilmu, arahan dan bimbingan selama penelitian.
5. Khohirul Hidayah, M.Si selaku Penguji II pada seminar proposal dan hasil yang
telah memberikan saran dan masukan yang membangun kepada Penulis.
6. Dian Banjar Agung, S.Hut., M.Sc yang telah memberikan izin dan kesempatan
untuk melakukan penelitian di Pusat Penyelamatan Satwa Tegal Alur.
7. Teman-teman seperjuangan dari Program Studi Biologi, UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta Angkatan 2016.
vi
Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu. Untuk itu penulis berharap saran dan kritik yang membangun agar laporan
ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi pembaca untuk menambah informasi
dan pengetahuan.
Jakarta, 19 November 2020
Penulis
vii
ABSTRAK
Abdul Bagas Alkatiri. Perilaku Makan dan Status Gizi Siamang Symphalangus
syndactylus Raffles, 1821) di Pusat Penyelamatan Satwa Tegal Alur, Jakarta.
Skripsi. Program Studi Biologi. Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020. Dibimbing oleh Fahma Wijayanti dan
Narti Fitriana.
Siamang (Symphalangus syndactylus Raffles, 1821) adalah salah satu jenis kera hitam
berlengan panjang terancam punah yang dilindungi oleh regulasi nasional dan
internasional, oleh karena itu upaya konservasi eksitu perlu dilakukan dengan
pengelolaan yang baik. Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tegal Alur Jakarta merupakan
satu-satunya tempat konservasi eksitu di bawah BKSDA Jakarta yang melakukan
pengelolaan siamang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku makan,
manajemen pengelolaan pakan dan status gizi siamang di PPS Tegal Alur. Penelitian
dilakukan pada bulan Maret - Juli 2020, dengan metode focal animal sampling dan ad
libitum sampling. Pengumpulan data manajemen pengelolaan pakan meliputi informasi
pemberian pakan dan jumlah pakan, sedangkan status gizi meliputi ciri fisik,
antropometri dan analisis komposisi pakan (energi, protein, karbohidrat, lemak dan air).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jadwal pemberian pakan siamang sudah sesuai
dengan waktu makan siamang di alam, yaitu pukul 07.00 WIB, 13.00 WIB dan 15.00
WIB. Pihak PPS Tegal Alur memberikan pakan berupa sembilan jenis buah, dua jenis
sayur dan satu jenis dedaunan. Siamang di PPS Tegal Alur sudah memenuhi jumlah
konsumsi pakan sesuai dengan bobot tubuhnya. Status gizi berdasarkan antropometri
menunjukkan bobot tubuh siamang belum sesuai dengan habitat alaminya. Pengamatan
morfologi memperlihatkan kondisi gigi dan mata siamang sehat, sedangkan beberapa
siamang memiliki kondisi rambut yang rontok dan mengalami depigmentasi. Kebutuhan
gizi belum memenuhi standar pada seluruh siamang karena zat protein yang terlalu
tinggi dan lemak yang terlalu rendah.
Kata kunci: Manajemen pakan; perilaku makan; PPS Tegal Alur; siamang; status gizi
viii
ABSTRACT
Abdul Bagas Alkatiri. Feeding Behavior & Nutritional Status of Siamang
Symphalangus syndactylus Raffles, 1821) at Tegal Alur Animal Rescue Center,
Jakarta. Undergraduate Thesis. Department of Biology. Faculty of Science and
Technology. State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019. Advised
by Fahma Wijayanti dan Narti Fitriana.
Siamang (Symphalangus syndactylus Raffles, 1821) is an endangered species of black
long-armed ape that is protected by national and international regulations, therefore
conservation efforts need to be carried out with good management. The Tegal Alur
Jakarta Animal Rescue Center (PPS) is the only existing conservation area under the
Jakarta BKSDA which manages gibbons. This study aims to analyze feeding behavior,
feed management and nutritional status of gibbons in PPS Tegal Alur. The study was
conducted in March - July 2020, using focal animal sampling and ad libitum sampling
methods. Food management data collection includes information on feeding and the
amount of feed, while nutritional status includes physical characteristics of the body,
anthropometry and analysis of feed composition (energy, protein, carbohydrates, fat and
water). The results showed that the feeding schedule for gibbons was in accordance with
the feeding times of gibbons in nature, namely 07.00 WIB, 13.00 WIB and 15.00 WIB.
PPS Tegal Alur provides food in the form of nine types of fruit, two types of vegetables
and one type of leaves. Siamang at Tegal Alur PPS has met the amount of feed
consumption according to body weight. The nutritional status based on anthropometry
shows that the body weight of the gibbon is not in accordance with its natural habitat.
Morphological observations showed that the gibbon’s teeth and eyes were healthy,
while some gibbons had hair loss and depigmentation. Nutritional needs have not met
the standards in all gibbons due to too high protein and too low fat.
Keywords: Feeding behavior; food management; nutritional status; siamang; Tegal
Alur animal rescue center
ix
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ...................................................................................................... v
ABSTRAK..................................................................................................................... viii
DAFTAR ISI ................................................................................................................... ix
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................... xi
DAFTAR TABEL .......................................................................................................... xii
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................. xiii
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ................................................................................................ 1
1.2. Rumusan Masalah........................................................................................... 3
1.3. Tujuan ............................................................................................................. 3
1.4. Manfaat ........................................................................................................... 4
1.5. Kerangka Berpikir .......................................................................................... 4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Siamang .......................................................................................................... 5
2.1.1. Perilaku ................................................................................................ 7
2.2. Pakan Siamang ............................................................................................... 8
2.3. Pemilihan Pakan Siamang ............................................................................ 10
2.4. Pusat Penyelamatan Satwa Tegal Alur ......................................................... 11
BAB III. METODE PENELITIAN
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian ........................................................................ 12
3.2. Alat dan Bahan Penelitian ............................................................................ 12
3.3. Metode Pengumpulan Data .......................................................................... 13
3.3.1. Penelitian Pendahuluan..................................................................... 13
3.3.2. Perilaku Makan ................................................................................. 13
3.3.3. Status Gizi......................................................................................... 14
3.3.4. Manajemen Pemberian Pakan .......................................................... 14
3.4. Analisis Data................................................................................................. 15
3.4.1. Aktivitas Harian ................................................................................ 15
3.4.2. Konsumsi Pakan ............................................................................... 15
3.4.3. Konsumsi Gizi .................................................................................. 15
3.4.4. Analisis Deskriptif ............................................................................ 16
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Kondisi Umum ............................................................................................. 17
4.1.1. Kondisi Lingkungan ......................................................................... 17
4.1.2. Kondisi Kandang .............................................................................. 19
4.1.3. Kondisi Satwa ................................................................................... 22
4.2. Manajemen Pakan ......................................................................................... 23
4.2.1. Waktu dan Cara Pemberian Pakan ................................................... 23
4.2.2. Pakan Siamang ................................................................................. 24
4.2.3. Palatabilitas Pakan ............................................................................ 25
4.2.4. Jumlah Konsumsi Pakan ................................................................... 27
x
4.3. Status Gizi..................................................................................................... 28
4.3.1. Ciri Fisik dan Antropometri ............................................................. 28
4.3.2. Konsumsi Nutrisi Pakan ................................................................... 33
4.4. Perilaku Harian ............................................................................................. 36
4.4.1. Perilaku yang Berhubungan Langsung dengan Pola Makan ............ 36
4.4.2. Perilaku yang Tidak Berhubungan Langsung dengan Pola Makan .. 42
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan ................................................................................................... 47
5.2. Saran ............................................................................................................. 47
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................... 48
LAMPIRAN - LAMPIRAN ......................................................................................... 54
xi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Kerangka Berpikir .......................................................................................... 4
Gambar 2. Aktivitas Bersuara Siamang (Symphalangus syndactylus) di Alam ................ 6
Gambar 3. Peta Kawasan PPS Tegal Alur ....................................................................... 12
Gambar 4. Kandang Siamang Betina dan Jantan di PPS Tegal Alur ............................. 19
Gambar 5. Tempat Makan dan Minum Siamang di PPS Tegal Alur .............................. 20
Gambar 6. Beberapa Postur Tubuh Siamang di PPS Tegal Alur .................................... 29
Gambar 7. Kondisi Rambut Siamang di PPS Tegal Alur ................................................ 31
Gambar 8. Morfologi Gigi Siamang di PPS Tegal Alur ................................................. 32
Gambar 9. Morfologi Mata Siamang di PPS Tegal Alur ............................................... 33
Gambar 10. Persentase Aktivitas Harian Siamang di PPS Tegal Alur ............................ 36
Gambar 11. Aktivitas Makan Siamang di PPS Tegal Alur ............................................. 37
Gambar 12. Aktivitas Minum Siamang Betina di PPS Tegal Alur ................................ 40
Gambar 13. Aktivitas Urinasi dan Defakasi Siamang Jantan di PPS Tegal Alur .......... 41
Gambar 14. Tekstur Feses Siamang di PPS Tegal Alur .................................................. 42
Gambar 15. Aktivitas Bergerak dan Bersuara Siamang di PPS Tegal Alur .................... 44
Gambar 16. Aktivitas Istirahat Siamang di PPS Tegal Alur ........................................... 45
xii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Jenis Tumbuhan Pakan Siamang di TSTJ dan THRWAR .................................. 9
Tabel 2. Urutan Pemilihan Pakan dan Bagian Yang Dikonsumsi di TSTJ .................... 11
Tabel 3. Kondisi Fisik Lingkungan Kandang ................................................................. 18
Tabel 4. Jenis Pakan Siamang di PPS Tegal Alur .......................................................... 25
Tabel 5. Palatabilitas Pakan Siamang di PPS Tegal Alur ............................................... 26
Tabel 6. Rata-rata Jumlah Pakan Siamang di PPS Tegal Alur ........................................ 28
Tabel 7. Hasil Pengamatan Ciri Fisik dan Antropometri Siamang di PPS Tegal Alur ... 30
Tabel 8. Konsumsi Gizi Pakan Siamang di PPS Tegal Alur .......................................... 34
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1. Pakan Siamang di PPS Tegal Alur ............................................................. 54
Lampiran 2. Perhitungan Rata-Rata Faktor Fisik Kandang Siamang Betina ................. 55 Lampiran 3. Perhitungan Rata-Rata Faktor Fisik Kandang Siamang Jantan ................. 55
Lampiran 4. Jumlah Pakan yang Diberikan Selama 14 Hari ......................................... 56
Lampiran 5. Jumlah Pakan Sisa ...................................................................................... 56 Lampiran 6. Jumlah Pakan yang Dikonsumsi ................................................................ 56
Lampiran 7. Kandungan Gizi Pakan Siamang di PPS Tegal Alur ................................. 57
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Siamang (Symphalangus syndactylus) adalah salah satu jenis kera hitam
berlengan panjang yang dilindungi oleh Peraturan Pemerintah (PP) Republik
Indonesia tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa liar, juga termasuk jenis
terancam punah prioritas berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: SK 180/IV-KKH/2015 (Ditjen
KSDAE, 2015). Pada tingkat internasional, siamang termasuk Appendix I
berdasarkan Convention on International Trade in Endangered Species of wild
fauna and flora (CITES) dan dikategorikan status genting (Endangared)
berdasarkan International Union for Conservation of Nature and Natural
Resources Red List (IUCN) 2016.
Siamang memiliki sebaran terbatas di Pulau Sumatera dan beberapa
wilayah Semenanjung Melayu. Populasi siamang di Pulau Sumatera yang tersisa
hanya menempati kawasan lindung dan konservasi. Menurut Yanuar (2009),
penurunan populasi siamang terjadi setidaknya 50% sejak 40 tahun terakhir.
Penurunan populasi siamang diakibatkan oleh perburuan untuk perdagangan
hewan peliharaan. Ditambah deforestasi habitat yang cepat akibat alih fungsi
lahan menjadi perkebunan kelapa sawit dan pembukaan lahan menjadi lahan
pertanian juga membuat populasinya berkurang di alam (Nijman dan Geissman,
2006). Masuknya siamang ke dalam daftar satwa langka membuat masyarakat
memiliki daya minat yang tinggi untuk memelihara primata tersebut. Oleh
karenanya dimasukan dalam Appendix I yang artinya dilarang dalam segala
bentuk perdagangan internasional dengan jumlahnya di alam kurang dari 800 ekor
(CITES, 2020). Namun demikian, sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat
akan konservasi cukup efektif dalam mengurangi jumlah masyarakat yang
memelihara satwa liar dilindungi. Hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat
yang menyerahkan satwa dilindungi kepada pihak berwajib.
Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi bertambahnya satwa liar yang
punah di alam. Salah satunya adalah didirikannya Pusat Penyelamatan Satwa
(PPS) di Bogor pada bulan Juli tahun 2000 yang merupakan hasil lokakarya
2
penanganan satwa liar yang dilindungi. Tujuan utama PPS adalah mengelola
satwa hasil sitaan atau penyerahan sukarela dari masyarakat untuk dirawat dan
direhabilitasi agar kemudian dapat dilepasliarkan kembali ke alam (YGI, 2006).
Dalam usaha pengelolaan tersebut, prinsip penting yang harus diperhatikan adalah
kesejahteraan satwa dengan membuat kondisi dimana kebutuhan hidup satwa
tersebut terpenuhi sesuai dengan habitat aslinya di alam. Salah satu faktor penentu
kelangsungan hidup satwa liar dan memegang peranan kunci dalam pengelolaan
satwa di PPS adalah pakan (Akbar, 2011). Keberhasilan usaha konservasi ini
didukung dengan informasi mengenai perilaku makan yang menyesuaikan dengan
perilaku satwa di alam.
Pemberikan pakan berupa sayur dan buah segar merupakan upaya
pemenuhan gizi berupa protein, lemak dan vitamin yang diperlukan dengan
menyesuaikan kebutuhan alaminya. National Research Council (2003),
merekomendasikan makanan untuk primata mengandung 15-22% protein
berdasarkan bahan kering, karena pada umumnya hewan akan makan untuk
memenuhi kebutuhan energi mereka. Kebutuhan energi primata juga meningkat
sekitar ¾ kekuatan massa tubuh, yang artinya primata perlu proporsi pakan yang
lebih tinggi dari berat tubuhnya dalam makanan setiap hari untuk memenuhi
keseimbangan nutrisinya. Kondisi primata yang sehat juga ditandai dengan
normalnya aktivitas harian yang dilakukan selama di kandang. Dalam
penelitiannya, Mahardika (2008) menunjukkan bahwa kondisi owa jawa di
penangkaran yang sehat dilihat dari normalnya keseluruhan aktivitas yang
dilakukan, yaitu primata tersebut akan makan saat merasa lapar, minum saat
merasa haus, melakukan aktivitas defekasi saat ingin defekasi dan juga aktivitas
lainnya. Penelitian di Javan Gibbon Center menyatakan bahwa primata lain
seperti owa jawa yang sehat, ditandai dengan tidak adanya luka disekujur tubuh
(Yohanna et al., 2014). Kesehatan fisik primata juga dapat dilihat dari sehatnya
kondisi rambut, gaya berjalan, nafsu makan, berat dan tinggi badan (National
Research Council, 1998).
Beberapa penelitian mengenai perilaku makan dan kandungan gizi pakan
siamang pada tempat konservasi eksitu telah dilakukan, namun belum ada yang
memperhatikan status gizi siamang dari kondisi kesehatan fisik dan
3
antropometrinya. Menurut Thamaria (2017), antropometri merupakan salah satu
metode penentuan status gizi dengan mengukur ukuran tubuh yang mencerminkan
perubahan karena adanya pertumbuhan. Tiyawati et al., (2016) dalam
penelitiannya menemukan bahwa siamang yang terdapat di Taman Agro Satwa
dan Wisata Bumi Kedaton diberikan pakan berupa ubi, kangkung, bayam, kacang
panjang, wortel, timun, dan pisang muli, dengan kandungan gizi terbesar yaitu
pisang muli dan termasuk dalam makanan yang paling banyak dikonsumsi per
harinya, yaitu 780 g. Penelitian Sharafina, (2017) menunjukkan bahwa jenis
pakan yang diberikan di Taman Satwa Taru Jurug, antara lain beberapa jenis
buah, sayur, tempe, telur dan daun, dengan jumlah konsumsi zat gizi tertinggi
pada siamang betina, yaitu energi sebesar 103,62 kal/bb/h, protein sebesar 3,72
g/bb/h, lemak sebesar 1,17 g/bb/h, karbohidrat sebesar 22,07 g/bb/h, dan air
sebesar 97,04 g/bb/h.
Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tegal Alur Jakarta merupakan satu-
satunya tempat konservasi eksitu dibawah BKSDA Jakarta yang melakukan
pengelolaan siamang. Siamang tersebut diperoleh sebagian besar dari hasil sitaan
petugas PPS atau penyerahan sukarela dari masyarakat. Manajemen pengelolaan
siamang saat ini bergantung pada informasi umum seluruh satwa di PPS.
Penelitian terkait perilaku makan, manajemen pengelolaan pakan dan status gizi
siamang di PPS perlu dilakukan dengan harapan dapat menunjang
keberlangsungan hidup siamang yang sesuai dengan perilaku dan kebutuhannya.
1.2. Rumusan Masalah
a. Bagaimana manajemen pemberian pakan siamang di PPS Tegal Alur?
b. Bagaimana status gizi siamang di PPS Tegal Alur?
1.3. Tujuan
a. Menganalisis manajemen pemberian pakan siamang pada PPS Tegal Alur.
b. Menganalisis status gizi siamang di PPS Tegal Alur.
4
1.4. Manfaat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan
informasi bagi pengelola PPS Tegal Alur dalam melakukan perbaikan
pengelolaan pakan siamang.
1.5. Kerangka Berpikir
Penelitian perilaku makan dan status gizi siamang (Symphalangus
syndactylus) di Pusat Penyelamatan Satwa Tegal Alur Jakarta memiliki kerangka
berpikir yang dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1. Kerangka berpikir penelitian perilaku makan dan status gizi siamang
(Symphalangus syndactylus) di Pusat Penyelamatan Satwa Tegal Alur,
Jakarta
Analisis Perilaku Makan dan Status Gizi Siamang (Symphalangus
syndactylus) di Pusat Penyelamatan Satwa Tegal Alur, Jakarta
Focal Animal
Sampling
- Suhu
- Kelembapan
- Kebisingan
- Intensitas cahaya
- Pemilihan
pakan
- Konsumsi
pakan
- Makan
- Minum
- Urinasi
- Defekasi
- Bergerak
- Grooming
- Istirahat
Perilaku
Makan
Aktivitas yang
mempengaruhi
pola makan
Aktivitas Harian Status
Gizi
Manajemen
Pemberian
Pakan
Lingkungan Kandang
PPS Tegal Alur
Siamang (Symphalangus syndactilus)
- Energi
- Protein
- Lemak
- Karbohidrat
- Air
- Berat badan
- Tinggi badan
- Mata
- Rambut
- Postur Tubuh
Ciri Fisik dan
Antropometri
Analisis
Proksimat
Pakan
5
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Siamang
Siamang (Symphalangus syndactylus) merupakan jenis kera hitam kecil
berlengan panjang yang termasuk keluarga Hylobatidae. Siamang memiliki
rambut hitam pekat yang hampir menutupi seluruh tubuhnya kecuali bagian muka
yang berwarna kecoklatan. Dibandingkan dengan keluarga Hylobatidae lainnya,
primata jenis ini berukuran lebih besar. Tubuhnya memiliki berat mencapai 11 kg,
dengan panjang 80-90 cm dan rentangan tangannya mampu mencapai 1,5 m.
Kantung suara pada leher memungkinkannya untuk bersuara keras dan dapat
menggelembung (BKSDA Lampung, 2007). Suara dikeluarkan secara bersama-
sama atau bersahutan antara jantan dan betina pasangannya. Kantung suaranya
mampu sebanding dengan ukuran kepala siamang saat sepenuhnya meningkat
(Supriatna & Ramadhan, 2016).
Siamang memiliki taksonomi sebagai berikut: Kingdom : Animalia;
Phylum : Chordata; Class : Mamalia; Order : Primata; Family : Hylobatidae;
Genus : Symphalangus; Spesies : Symphalangus syndactylus (Raffles, 1821)
bersinonim dengan Hylobates syndactylus, Symphalangus continentis,
Symphalangus gibbon, Symphalangus subfossilis dan Symphalangus volzi
(Nijman & Geissman, 2008). Jenis yang mendiami semenanjung Malaysia dan
Sumatera telah dianggap subjenis yang berbeda. S. syndactylus terbagi menjadi
dua subjenis yaitu S.s. syndactylus yang tersebar di Pulau Sumatera dan disebut
siamang Sumatera dan S.s.continentis yang tersebar di wilayah semenanjung
Malaysia dan disebut siamang Malaysia (Supriatna & Ramadhan, 2016). Siamang
juga terdapat di daerah kecil semenanjung Thailand (Nijman & Geissman, 2008).
Nama lokal dikenal dengan siamang, atau kimbo di beberapa daerah Pulau
Sumatera, imbo sebutan siamang untuk masyarakat suku batak di Sumatera Utara.
Hylobatidae memiliki habitat asli hanya di Asia Tenggara dan sekitarnya
termasuk sebagian wilayah Indonesia. Terdapat 3 jenis di Pulau Sumatera, yaitu
H. agilis, H. lar dan S. Syndactylus (Geissmann, 1995).
6
Gambar 2. Aktivitas bersuara siamang (Symphalangus syndactylus) di alam
(Fountain, 2011). Garis putih horizontal di bawah gambar sampel
menunjukkan skala 30 cm
Siamang tidak memiliki ekor, namun terdapat rumbai genital mengarah ke
bawah sepanjang 13,5 cm dan mirip ekor yang dapat dijumpai pada pejantan.
Terdapat semacam selaput kulit (web) yang dapat dijumpai pada penyatuan antara
jari kedua dan ketiga pada tangannya, kondisi tersebut tercermin dari nama ilmiah
jenis. Terkadang jari keempat dan kelima juga berselaput. Subjenis pada siamang
dibedakan dari morfologi hidung (Supriatna & Ramadhan, 2016). Menurut
Kuswanda & Garsetiasih (2016), bobot tubuh siamang sangat bervariasi sesuai
kelas umur sebagai berikut:
a. Rata-rata bayi dan anak (1-4 tahun) diperkirakan 0,6-4 kg,
b. Muda dan remaja (5-6 tahun) di atas 4-7 kg,
c. Sub remaja (7-8 tahun) di atas 7-10 kg, dan
d. Dewasa (di atas 9 tahun) untuk betina 10,5 kg dan jantan 12,8 kg.
Habitat siamang dari hutan dataran rendah (> 300 mdpl) hingga hutan
primer dataran tinggi 1.500 mdpl sampai 1828,8 mdpl (Nijman & Geissman,
2008) hingga 3.800 mdpl. Tiga jenis Hylobatidae tinggal di hutan hujan tropis
Sumatera, yaitu siamang (Symphalangus syndactylus), owa tangan putih (H. lar),
dan ungko (H. agilis) (Mubarok, 2012). Di Provinsi Sumatera Utara, siamang
tercatat dapat ditemukan di Cagar Alam Dolok Sipirok, Taman Nasional Gunung
Leuser, kawasan hutan Batang Toru (Mubarok, 2012).
Berdasarkan perlindungan dalam negeri, siamang termasuk satwa yang
telah dilindungi undang-undang dan peraturan perlindungan satwa liar pada tahun
1931, selanjutnya Menteri Pertanian mengeluarkan SK pada tanggal 14 Februari
1973 No. 66/Kpts/um/2/1973, SK Menteri Kehutanan 10 Juni 1991 No. 301/Kpts-
II/1991 dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 (Rosyid, 2007). Peraturan
7
terakhir menyebutkan bahwa siamang termasuk satwa dilindungi dalam Permen
LHK No. P.20/MENLHK /SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan
satwa yang dilindungi. Perlindungan luar negeri seperti IUCN (International
Union on Conservation for Nature) Redlist Version 2014, menempatkan siamang
pada kategori terancam punah (Endangered), yang artinya dalam waktu
mendatang akan menghadapi risiko kepunahan yang tinggi di alam liar (Tiyawati
et al., 2016). Kemudian berdasarkan ketentuan perdangangan satwa liar, CITES
(Convention on International trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora), siamang termasuk Appendix I, yaitu jumlah yang sangat sedikit di alam,
dikhawatirkan akan punah dan larangan keras segala bentuk perdagangan
internasional secara komersil.
2.1.1. Perilaku
Siamang menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pohon (arboreal).
Pergerakan siamang biasanya dibagi dalam empat kelompok utama, yaitu
climbing, leaping, brakiasi dan bipedal walking. Menurut WCS-IP (2000),
pergerakan yang paling umum dilakukan siamang adalah brakiasi, sedangkan
memanjat (climbing) berkisar 9-11%, berjalan dengan dua kaki (bipedal walking)
berkisar 8-11% dan melompat (leaping) berkisar 1-2%. Aktivitas harian siamang
dapat dikategorikan sebagai berikut:
1) Aktivitas Istirahat
Aktivitas istirahat ditandai dengan turunnya siamang ke bagian tajuk
paling rendah untuk menghindari teriknya sinar matahari (Yuliana, 2011).
Siamang memanfaatkan periode tidak aktif ini dengan berinteraksi sosial dengan
anggota kelompoknya seperti mencari kutu, menelisik dan bermain dengan
anaknya (Harianto, 1998).
2) Aktivitas Makan
Makan merupakan aktivitas yang sebanding dengan waktu istirahatnya
dibanding dengan aktivitas bergerak. Aktivitas ini memakan waktu yang besar
setiap harinya. Berkaitan dengan ketersediaan pakan dan perilaku makannya,
siamang sangat selektif dalam memilih pakannya (Harianto, 1998). Menurut
Chivers (1974), siamang menghabiskan 25% untuk makan dari aktivitas
8
hariannya. Aktivitas ini sangat aktif dilakukannya saat siang hari sampai matahari
terbenam (Andriansyah, 2005).
3) Aktivitas Berpindah
Aktivitas berpindah terbagi menjadi empat tipe, yaitu memanjat, berjalan,
brakiasi dan melompat. Atmanto et al. (2014) menuturkan bahwa pergerakan
siamang sebagian besar (81,64%) dilakukan dengan cara brakiasi. Dalam satu
hari, siamang mampu bergerak sampai 1 km dengan luas teritorialnya sekitar 47
ha (Supriatna & Ramadhan, 2016). Saat melakukan penjelajahan di wilayahnya,
betina lebih sering memimpin dibanding jantan (Chivers, 1974). Andriansyah
(2005) menambahkan individu betina sering terlihat berjalan terlebih dahulu dan
kadang menunggu untuk beberapa saat kemudian kembali ke belakang jika
anggota yang lain tidak mengikuti.
4) Aktivitas Bersuara
Berbeda dengan aktivitas siamang di alam, bersuara merupakan salah satu
aktivitas pertama yang biasa dilakukan di penangkaran (Sari & Sugeng, 2015).
Semua jenis Hylobatidae menghasilkan suara atau vokalisasi menyerupai
nyanyian dengan pola yang spesifik dan biasanya dilakukan pada pagi hari
(Nijman & Geissman, 2006). Dalam penelitiannya di Taman Agro Satwa dan
Wisma Bumi Kedaton, siamang melakukan aktivitas bersuara hampir di setiap
kegiatannya (Tiyawati et al., 2016). Siamang aktif bersuara jika banyak
pengunjung dan pada pukul 11.00 WIB – 13.00 WIB. Kegiatan bersuara
merupakan kegiatan yang selalu dilakukan oleh kelompok siamang yang
berfungsi untuk mempertahankan dan menunjukkan teritorialnya serta pengaturan
ruang antar kelompok (spacing mechanism) (Rinaldi, 1992).
2.2. Pakan Siamang
Fleagle (1988) mengategorikan sumber pakan menjadi tiga, yaitu:
1) Struktural, yaitu bagian tumbuhan yang meliputi daun, batang, cabang dan
materi tumbuhan lainnya yang mengandung struktur karbohidrat (selulosa);
2) Bagian reproduktif, yaitu organ tumbuhan seperti tunas bunga, bunga dan
buah (matang atau mentah);
9
3) Materi dari hewan, yaitu makanan yang berasal dari hewan baik vertebrata
maupun invertebrata.
Tabel 1. Jenis tumbuhan pakan siamang di Taman Satwa Taru Jurug, Surakarta
dan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Andriansyah, 2005;
Sharafina, 2017)
Kelompok Nama lokal Nama ilmiah
Buah
Nanas Ananas comosus
Mentawa Arthocarpus anisophylus
Pepaya Carica papaya
Semangka Citrullus lonatus
Jeruk Citrus sinensis
Melon Cucumis melo
Timun Cucumis sativus
Simpur Dillenia aurea
Jenitri Elaucarpus sphaericus
Tanaman salam Eugenia polyantha
Tin Ficus carica
Nyawai Ficus fariegata
Fikus Ficus fulva
Rukem Flacuurtia rukem
Petai Leucaena aurea
Litsea Litsea firma
Pisang Musa sp.
Bengkuang Pachyrrhizus erosus
Apel Pyrus malus
Trembesi Samanea saman
Surian Toona sureni
Jagung rebus Zea mays
Sayur Wortel Daucus corota
Kacang panjang Vigna Sinensis
Olahan Tempe rebus -
Telur ayam rebus -
Siamang adalah satwa liar yang sangat selektif memilih pakan. Pakan
utama siamang di habitat aslinya yaitu buah-buahan yang matang dan daun muda
(Rosyid, 2007a). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Atmanto et al.
(2014), jenis daun yang merupakan pakan alami siamang adalah ara (Ficus sp.),
aseman (Polygonum chinense), kenanga (Cananga odorata), nangkan (Palaquium
rostatum), kiteja (Cinnamomum inners), kemang (Mangifera caesia), Sempu air
(Dillenia excelsa), mengris (Kompassia excelsa), dan Polyalthia grandiflora.
Sedangkan jenis tumbuhan pakan buah siamang di alam, yaitu ara (Ficus sp.),
10
aseman (Polygonum chinense), deluak (Grewia paniculata), gandaria (Bouea
macrophylla), kenaren (Dacryodes rostrata), pelangas (Aporosa aurita) dan sapen
(Aplaia palembanica).
Selain kebutuhan pakan daun dan buah, siamang sering terlihat memakan
serangga-serangga kecil yang ada di dinding kandang, hal ini dikarenakan
siamang termasuk satwa omnivora dengan jenis pakan berupa daun, buah, bunga,
serangga dan binatang kecil lainnya. International center for Gibbon Studies,
California memberikan pakan siamang berupa apel, bayam, wortel, brokoli, kiwi,
seledri, ubi jalar, pisang dan selada (Mootnick, 1997). Berdasarkan penelitian
Sharafina (2017), di Taman Satwa Taru Jurug, siamang diberi pakan yang
komersial, seperti buah, sayur, tempe dan telur ayam, juga pakan non komersial
seperti daun, sedangkan dalam penelitian (Andriansyah, 2005) di Taman Hutan
Raya Abdul Rachman, siamang diberi pakan berupa buah (Tabel 1).
2.3. Pemilihan Pakan Siamang
Pemilihan pakan adalah urutan pakan yang dikonsumsi oleh satwa.
Berdasarkan penelitian Sharafina (2017), urutan pengambilan pakan siamang di
Taman Satwa Taru Jurug hampir sama setiap harinya dengan makanan yang
disukai yaitu buah-buahan, terutama nanas dan apel. Selanjutnya, jenis pakan
yang terakhir dikonsumsi oleh siamang jantan dan disukai oleh siamang betina
yaitu bengkuang. Perbedaan preferensi pakan antara siamang jantan dan betina di
penangkaran dapat disebabkan karena pola makan terdahulu yang berbeda
sebelum dirawat oleh pihak penangkaran, perilaku harian dan fisiologis
(Rasmada, 2008). Umumnya, kebutuhan makanan satwa jantan lebih tinggi
dibandingkan dengan satwa betina. Kondisi kesehatan satwa juga merupakan
faktor yang mampu mempengaruhi jumlah konsumsi pakan (Masy’ud & Ginoga,
2016).
11
Tabel 2. Urutan pemilihan pakan dan bagian yang dikonsumsi di Taman Satwa
Taru Jurug (Sharafina, 2017)
Kelompok Jenis pakan
Urutan
pemilihan pakan Bagian yang
dikonsumsi Jantan Betina
Buah Apel 2 1 Buah, kulit buah
Bengkuang 14 4 Buah
Jagung rebus 5 9 Biji
Jeruk 9 8 Buah, biji
Melon 8 7 Buah
Nanas 6 3 Buah, kulit buah
Pepaya 4 13 Buah, daun
Pisang 3 12 Buah
Semangka 7 6 Buah, kulit buah
Timun 10 5 Buah, kulit buah
Sayur Kacang panjang 12 14 Biji
Wortel 13 10 Umbi
Olahan Tempe rebus 11 11 Semua bagian tempe
Telur ayam rebus 1 2 Putih dan kuning telur
Biasanya, buah musim seperti apel, jeruk dan melon menjadi primadona
pakan siamang jantan dan betina (Sharafina, 2017). Siamang cenderung
mengkonsumsi buah yang memiliki warna menarik, rasa yang cukup enak, manis
asam dan sepah (Atmanto et al., 2014). Di habitat alaminya, pakan utama siang
berupa buah-buahan matang dan pucuk daun muda (Rosyid, 2007a).
2.4. Pusat Penyelamatan Satwa Tegal Alur
Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) merupakan salah satu program nasional
dalam membantu penanganan satwa liar sebagai hasil konsekuensi upaya
penegakan hukum di bidang konservasi satwa liar melalui kegiatan penertiban dan
kampanye penyelamatan satwa liar yang dilindungi di Indonesia. Kebutuhan dan
kesepakatan adanya program ini didasarkan kepada tindak lanjut Lokakarya
Penanganan Satwa Liar Peliharaan yang Dilindungi (SPL) di Bogor pada tanggal
20-21 Juli 2000. Lokakarya ini telah menghasilkan 11 rekomendasi penting, dan
satu di antaranya adalah kebutuhan akan fasilitas pengelolaan satwa liar
dilindungi, dari hasil proses penegakan hukum. Dalam konteks internasional,
Indonesia sebagai salah satu anggota CITES menyepakati resolusi untuk
menyediakan fasilitas transit satwa. Pusat Penyelamatan Satwa merupakan
program hasil kerjasama Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi
12
Alam Departemen Kehutanan Republik Indonesia (Ditjen PHKA Dephut RI),
dengan The Gibbon Foundation dan beberapa LSM di Indonesia (Prayudhi,
2015).
Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tegal Alur adalah tempat transit
sementara satwa liar dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta
(BKSDA Jakarta), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PPS ini
merupakan salah satu lembaga konservasi eksitu yang memiliki peran penting
untuk mendukung konservasi satwa liar secara insitu. Satwa tersebut berasal dari
hasil sitaan, temuan atau penyerahan dari masyarakat yang dirawat sementara
sebelum adanya penetapan penyaluran satwa (animal disposal) oleh Dirjen
KSDAE untuk pelepasliaran maupun translokasi ke Lembaga
Konservasi/Penangkaran. PPS Tegal Alur merupakan PPS yang paling banyak
melakukan translokasi satwanya ke beberapa PPS lain seperti PPS Cikananga, hal
ini dikarenakan lokasinya yang berdekatan dengan bandara Soekarno Hatta
sehingga apabila terdapat satwa yang ingin diperdagangkan dan disita oleh
petugas bea cukai bandara, maka satwa tersebut akan diserahkan ke PPS Tegal
Alur (Rino, 2009).
12
BAB II
METODE PENELITIAN
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan, yaitu pada bulan Maret – Juli
2020. Lokasi penelitian di PPS Tegal Alur, Jakarta tepatnya pada kawasan
kandang siamang (Gambar 3). Kegiatan pengambilan data dilakukan pada 3 bulan
pertama dan 2 bulan selanjutnya digunakan untuk kegiatan pengolahan dan
analisis data.
Gambar 3. Peta kawasan PPS Tegal Alur
3.2. Alat dan Bahan Penelitian
Peralatan yang digunakan untuk kegiatan pengamatan dan pengambilan
data, yaitu kamera, alat tulis, jam tangan, timbangan, termometer udara,
higrometer, lux meter, sound level meter, panduan wawancara dan tally sheet.
Objek penelitian adalah lima individu siamang jantan dewasa (Sapri, Pixy, Gigih,
Mency & Patrick) dan satu individu betina dewasa (Noni). Umur siamang dewasa
mengacu pada Santosa et al., (2010), yaitu di atas 6 tahun. Siamang-siamang
tersebut adalah satwa hasil sitaan BKSDA dan penyerahan dari masyarakat.
13
3.3. Metode Pengumpulan Data
3.3.1 Penelitian Pendahuluan
Penelitian pendahuluan (preliminary) terlebih dahulu dilakukan sebelum
dimulainya pengambilan data penelitian. Preliminary bertujuan untuk
mendapatkan informasi aktivitas yang berhubungan dengan makan dan aktivitas
yang mempengaruhi pola makan siamang. Preliminary juga bertujuan untuk
mendekatkan pengamat pada satwa sebagai adaptasi. Metode yang digunakan
dalam penelitian preliminary adalah ad libitum, yaitu mengamati semua perilaku
pada siamang.
3.3.2. Perilaku Makan
Perilaku makan yang diamati dalam penelitian ini adalah palatabilitas
pakan, yaitu pengamatan urutan pemilihan dan pengambilan jenis pakan yang
dikonsumsi. Jenis pakan yang paling disukai oleh siamang yang diindikasikan
oleh banyaknya jumlah konsumsi jenis makanan tersebut. Urutan pengambilan
pakan diamati dengan cara melihat dari jenis pakan yang pertama kali dikonsumsi
oleh siamang sampai jenis pakan yang terakhir dikonsumsi oleh siamang.
Pengamatan aktivitas harian dilakukan selama 14 hari pengamatan untuk
masing-masing jenis kelamin. Pengamatan dimulai pukul 07.00 WIB – 16.00
WIB. Metode yang digunakan yaitu focal animal sampling, metode pengambilan
sampel yang berfokus pada satu individu atau unit yang diamati untuk jangka
waktu tertentu dalam pengamatan tingkah laku. Metode ini bertujuan untuk
mengetahui semua jenis tingkah laku yang dilakukan oleh individu yang diamati
(Altmann, 1974). Pencatatan perilaku siamang dilakukan dengan metode
Instantaneous, yaitu dengan mencatat perilaku siamang pada waktu atau periode
tertentu.
Kemudian pengamatan aktivitas siamang yang berhubungan langsung
dengan aktivitas makan, terdiri dari:
a. Aktivitas makan, yaitu memasukkan makanan ke dalam mulut, mengunyahnya
dan kemudian menelannya.
b. Aktivitas minum, yaitu memasukkan air/cairan ke dalam tubuh melewati
mulutnya.
14
c. Aktivitas defekasi, yaitu aktivitas mengeluarkan kotoran dalam bentuk padat.
d. Aktivitas urinasi, yaitu aktivitas mengeluarkan kotoran berbentuk cair.
Selain aktivitas yang berhubungan langsung dengan perilaku makan,
dilakukan juga pengamatan aktivitas harian yang mempengaruhi pola makan
siamang. Aktivitas yang diamati terdiri dari:
a. Lokomosi, yaitu aktivitas menggerakkan tubuh dengan cara berpindah dari
tempat yang satu ke tempat yang lain, bermain dan bersuara.
b. Grooming, yaitu aktivitas membersihkan diri atau merawat tubuh seperti,
menjilat dan menggaruk.
c. Istirahat, yaitu tidak adanya aktivitas yang terjadi, apabila siamang dalam
keadaan diam atau tidur dan duduk.
3.3.3. Status Gizi
Indikator penentuan status gizi dilihat dari ciri-ciri fisik, antropometri dan
analisis komposisi pakan. Ciri fisik primata yang diamati antara lain tanda fisik
pada tubuh, postur tubuh, rambut dan mata siamang. Selanjutnya antropometri,
yaitu salah satu metode penentuan status gizi dengan mengukur ukuran tubuh
yang mencerminkan perubahan karena adanya pertumbuhan (Thamaria, 2017).
Data antropometri berupa bobot tubuh dan tinggi siamang. Analisis komposisi
pakan dilakukan bersamaan dengan pengamatan perilaku makan. Setelah dilihat
komposisi pakan, dilanjutkan menganalisis nilai kandungan gizi dan kebutuhan
pakan yang dikonsumsi. Data dianalisis berdasarkan tabel komposisi pangan
Indonesia (PERSAGI, 2008) dengan menggunakan rumus konsumsi gizi tiap jenis
pakan. Konsumsi gizi pakan yang dinilai terdiri atas konsumsi energi, protein,
lemak, karbohidrat dan air.
3.3.4. Manajemen Pemberian Pakan
Data manajemen pakan akan dikumpulkan saat pengamatan meliputi
pembagian pakan, waktu pemberian pakan, cara pemberian pakan, jenis pakan
yang meliputi kelompok buah, sayur, serangga dan lain-lain, jumlah pakan yang
diberikan dan dikonsumsi (berat tiap pakan). Bobot pakan yang diberikan pada
satu hari ditimbang untuk setiap jenisnya dan sisa pakan keesokan harinya yang
15
masih berada di dalam kandang dikumpulkan dan ditimbang per jenis pakan
(Rahman, 2011).
Pengumpulan data lingkungan kandang meliputi kondisi kandang dan
faktor fisik lingkungan sekitar kandang. Kondisi kandang siamang meliputi
ukuran, alas, tempat pemberian pakan dan jeruji kandang. Faktor fisik yang diukur
meliputi pengukuran suhu, kelembapan, intensitas cahaya dan kebisingan.
Pencatatan faktor fisik dilakukan pada pagi pukul 07.00 WIB, siang pada pukul
12.00 WIB, dan sore hari pada pukul 15.00 WIB.
3.4. Analisis Data
3.4.1. Aktivitas Harian
Analisis aktivitas harian dilakukan dengan menguraikan segala bentuk
aktivitas yang nampak dalam sebuah katalog berbentuk ethogram. Persentase
aktivitas setiap individu adalah sebagai berikut :
% Aktivitas =
Keterangan:
X = Frekuensi/lama suatu perilaku dilakukan
Y = Total frekuensi pengamatan/total waktu (Altmann, 1974)
3.4.2. Konsumsi Pakan
Banyaknya pakan yang dikonsumsi per hari dihitung rata-ratanya selama
pengamatan dan dihitung selisih antara sebelum dan sesudah pemberian pakan.
Besarnya konsumsi setiap jenis pakan dihitung dengan cara sebagai berikut:
K = g0-g1
Keterangan:
K= konsumsi pakan (g)
g0= berat pakan semula (g)
g1= berat sisa pakan yang diberikan (g) (Sharafina, 2017)
3.4.3. Konsumsi Gizi
Kandungan gizi pakan siamang diperoleh melalui data sekunder. Informasi
kandungan gizi diperoleh dari hasil analisis proksimat pada penelitian sebelumnya
yang dilakukan oleh Rahman (2011). Analisis proksimat yaitu analisis kimia
untuk mengetahui kandungan zat makanan yang terdapat di dalam bahan
16
makanan. Besarnya konsumsi gizi setiap jenis pakan dihitung dengan cara sebagai
berikut.
K =
Keterangan:
K= konsumsi gizi pakan (g)
a = berat pakan semula (g)
b = kandungan gizi dalam 100 g (kkal atau g)
%BDD = berat dapat dimakan (Sharafina, 2017)
3.4.4. Analisis Deskriptif
Data yang sudah dianalisis secara kuantitatif, kemudian dianalisis dengan
cara deskriptif dengan cara dibuat dalam bentuk tabel dan grafik/diagram. Hasil
tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam suatu kalimat yang dapat menjelaskan
dan menyimpulkan hasil penelitian.
17
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Keadaan Umum
4.1.1. Kondisi Lingkungan
Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tegal Alur terletak di Jl. Benda Raya,
Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Kawasan PPS dikelilingi oleh Taman
Pemakaman Umum (TPU) Tegal Alur dengan bagian depan kawasan berbatasan
langsung dengan jalan raya. Lokasi kandang satwa, termasuk siamang terletak
kurang lebih 120 m dari jalan raya. Lokasi kandang siamang terdapat pada bagian
paling belakang kawasan PPS dengan beberapa primata dan mamalia besar
lainnya, yaitu owa jawa, lutung jawa, beruang madu dan binturong. Kandang yang
berdekatan dengan primata lain biasanya memicu adanya suara bising karena
primata yang saling bersahutan satu sama lain. Kebisingan lainnya ditimbulkan
oleh suara kendaraan bermotor yang lewat, terutama yang berukuran besar. Pakan
siamang bersumber dari dapur pakan yang letaknya paling belakang kawasan PPS
dengan jarak ke kandang siamang sekitar 10 m.
Letaknya yang berada pada ketinggian 18 m di atas permukaan laut
membuat adanya perbedaan faktor fisik dengan habitat alaminya. Di habitat
alaminya, siamang umum dijumpai pada ketinggian di atas 300 mdpl, tepatnya
pada hutan dataran rendah (Kuswanda et al., 2019). Satwa yang ditempatkan di
PPS memiliki waktu adaptasi yang berbeda-beda. Beberapa siamang di PPS sudah
cukup beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, namun ada juga siamang yang
masih terlihat takut dan stres. Keadaan tersebut ditandai dengan sikap atau
gerakan yang tiba-tiba menjadi aktif saat keeper atau peneliti lewat depan
kandang. Walaupun sifat dan fungsi dari PPS adalah sebagai tempat sementara
beberapa satwa untuk dilepasliarkan kembali, tetapi satwa yang ditempatkan di
PPS perlu mengalami adaptasi untuk menyesuaikan dengan kondisi sekitarnya.
Faktor eksternal yang mempengaruhi aktivitas harian siamang antara lain,
suhu udara, kelembapan udara, kebisingan dan intensitas cahaya. Pada saat suhu
udara yang tinggi dan kelembapan udara yang rendah siamang akan mengurangi
aktivitasnya selama di kandang dan lebih banyak beristirahat, atau sekedar
18
membersihkan bagian tubuhnya (grooming). Hasil pengukuran faktor fisik
lingkungan kandang selama pengamatan menunjukkan bahwa rata-rata suhu udara
sebesar 31.05±0,17 oC (pagi), 31,50±0,08 oC (siang) dan 30,22±0,09 oC (sore),
sedangkan rata-rata kelembapan udara sebesar 66,29±0,51 % (pagi), 64,79±0,1 %
(siang) dan 67,21±0,91 % (sore) (Tabel 4).
Suhu yang meningkat dan kelembapan yang rendah di siang hari
menyebabkan udara menjadi sangat panas. Keadaan tersebut membuat siamang
lebih banyak melakukan aktivitas beristirahat dan tidak banyak melakukan
aktivitas bergerak. Kondisi cuaca pada pagi hari cukup sejuk karena suhu yang
rendah dan kelembapan yang tinggi. Hal ini menyebabkan siamang banyak
melakukan pergerakan dan menghangatkan tubuhnya dengan mencari sinar
matahari. Apabila dibandingkan dengan suhu dan kelembapan udara di habitat
alaminya, kondisi di PPS Tegal Alur kurang optimum. Menurut Kuswanda et al.
(2019), suhu dan kelembapan yang stabil dan ideal bagi siamang di habitat
aslinya, yaitu antara suhu 18 oC – 25 oC dan rata-rata kelembapan udara 70% –
100%.
Tabel 3. Rata-rata kondisi fisik lingkungan kandang
Waktu (WIB) Suhu udara
(oC)
Kelembapan
udara (%)
Kebisingan
(dB)
Intensitas cahaya
(Lux)
07.00 (pagi) 31,05±0,17 66,29±0,51 48,32±0,35 5185,43±2025.08
13.00 (siang) 31,50±0,08 64,79±0,1 45,38±0,06 3642,04±1298.21
16.00 (sore) 30,22±0,09 67,21±0,91 46,28±1,26 2314,89±1630.84
Sumber kebisingan di kawasan PPS didominasi oleh suara saut-sautan
primata, suara burung dan suara kendaraan bermotor. Rata-rata kebisingan
terbesar terdapat pada pagi hari, yaitu sebesar 48,32±0,35 dB (Tabel 3). Pagi hari
merupakan waktu aktif bagi satwa di kawasan PPS dalam melakukan aktivitas
bersuara, seperti apa yang dilakukan oleh satwa burung jenis elang dan paruh
bengkok. Terkadang siamang pada pagi hari juga mengeluarkan suara bisingnya
melalui kantung suara (gullar sac), kemudian dilanjutkan dengan saut-sautan
dengan primata lain seperti owa jawa. Penyumbang terbesar suara kendaraan
bermotor di pagi hari adalah mobil-mobil besar seperti truk pengangkut barang.
Tingkat kebisingan di kawasan PPS Tegal Alur masih jauh dibawah batas baku
19
mutu kebisingan berdasarkan keputusan menteri lingkungan hidup No. 48 tahun
1996 untuk lingkungan kegiatan maksimal 55 dB. Meskipun sudah terbiasa
dengan suara tersebut, pengelola harus tetap melakukan pengecekan harian karena
dikhawatirkan siamang mengalami ketakutan atau stres.
4.1.2. Kondisi Kandang
Secara umum letak kandang di PPS Tegal Alur saling berdekatan dengan
satwa lain sehingga mempengaruhi aktivitas satwa lainnya terutama siamang.
Sistem perkandangan di PPS Tegal Alur umumnya dibuat memungkinkan adanya
udara bebas keluar masuk kandang, sehingga ventilasi udaranya cukup baik.
Kandang berventilasi menjamin adanya aliran udara yang terus menerus melewati
kandang dan sekitar satwa (Tillman et al., 1991). Anggraeni (2006)
menambahkan, kondisi kandang berventilasi mencegah adanya debu dan bau-
bauan yang mempengaruhi kondisi satwa di kandang.
(A) (B)
Gambar 4. Kandang siamang betina (A) dan jantan (B) di PPS Tegal Alur
Letak kandang siamang jantan dan betina memiliki jarak sekitar 15 m.
Kedua kandang berbentuk rumah panggung sehingga mudah dibersihkan karena
feses dan urine langsung jatuh ke bawah. Kandang siamang betina berukuran 2 m
(p) x 2 m (l) x 1 m (t), sedangkan kandang siamang jantan berukuran 3 m (p) x 2
m (l) x 2,5 m (t) (Gambar 4). Dinding kedua kandang siamang dibatasi dengan
ubin. Pada bagian atap, depan dan alas kandang terbuat dari besi galvanis. Pada
kandang betina terdapat tempat pakan permanen berbentuk seperti laci bervolume
20 cm2, sedangkan kandang jantan berbentuk seperti laci setengah lingkaran
bervolume 30 cm2 di bagian depan kandang (Gambar 5).
20
(A) (B) (C)
Gambar 5. Tempat minum (A) - makan siamang betina (B) dan jantan (C) di PPS
Tegal Alur
Posisi kandang siamang yang berbatasan langsung dengan satwa lain
membuat kemungkinan adanya interaksi satwa satu sama lain. Oleh karena itu
asbes putih di kandang siamang betina dipasang oleh pengelola PPS dengan
tujuan agar siamang tidak melakukan kontak fisik kepada satwa tetangga.
Kandang siamang betina berbatasan langsung dengan satwa binturong (Arctictis
binturong) dan lutung jawa timur (Trachypithecus auratus), sedangkan kandang
individu-individu siamang jantan berbatasan langsung dengan beruang madu
(Helarctos malayanus). Salah satu faktor penting dalam upaya modifikasi
kandang yang sesuai dengan habitat alaminya, pengelola melakukan beberapa
pengayaan di dalam kandang siamang. Kandang betina ditempatkan tali ban karet
dan batang pohon, sedangkan kandang jantan ditempatkan ban bekas, tali ban
karet dan tempat istirahat siamang yang terbuat dari kayu kaso.
Kandang merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan
kesejahteraan hewan. Peningkatan kualitas ruang kandang mampu meningkatkan
kesejahteraan hewan untuk memungkinkan melakukan pergerakan, eksplorasi dan
mengekspresikan perilaku alaminya. Belum ada standar khusus dalam penentuan
kualitas kandang untuk tempat penyelamatan satwa (animal rescue center).
Melalui pendekatan dengan standar kebun binatang, menurut Exhibited Animals
Protection (2000) tentang kebijakan yang berkaitan dengan kondisi primata di
kebun binatang, ukuran minimum kandang dengan maksimum tinggi siamang 89
cm, yaitu sebesar 9 m (p) x 13,5 m (l) x 4 m (t). Kandang yang ditempati siamang
jantan ialah kandang terbesar untuk kategori mamalia besar. Pengelola PPS perlu
memperhatikan ukuran kandang untuk siamang betina dikarenakan ukurannya
yang berbeda dengan ukuran kandang jantan dan jauh dari standar yang
ditetapkan oleh Exhibited Animals Protection (2000). Perkins (1992) menemukan
21
bahwa tingkat aktivitas orang utan meningkat dengan ukuran kandang yang lebih
luas.
Hal penting lainnya dalam menunjang kualitas kandang adalah bagaimana
primata memanfaatkan ruang yang tersedia untuk mereka beraktivitas. Pada
beberapa modifikasi satwa arboreal seperti primata, pengayaan kandang dapat
difokuskan pada akses bidang vertikal (Anderson, 2014). Menurut Ross et al.
(2011) kandang yang luas tidak terlalu penting bagi kesejahteraan hewan daripada
kompleksitas dan kegunaan ruang di dalamnya. Dengan menambahkan furnitur
yang membuat bagian ruang tengah dan atas dapat diakses, membuat area
kandang menjadi lebih berguna (Maple & Perkins, 1995). Pendekatan
rekomendasi oleh Sian (2002) di Kebun Binatang Ragunan yang memiliki luas
kandang siamang sebesar 2,5 m (p) x 2 m (l) x 3 m (t) , antara lain perlu dilakukan
pengayaan kandang primata, seperti cabang, tali, kayu gelondongan untuk
memberi hewan banyak aktivitas yang dapat dikerjakan di kandangnya.
Yohanna et al. (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa di Javan
Gibbon Center (JGC) kondisi kandang pada primata lain seperti owa jawa
dibedakan menjadi dua, yaitu kandang introduksi dan kandang pasangan. Kedua
kandang ini memiliki perbedaan yang jelas pada jenis kandang, lantai kandang
dan kondisi saluran kandang. Berbeda dengan PPS Tegal Alur, kebersihan lantai
kandang di JGC masih ditemukan feses yang menumpuk pada tanah, karena lantai
berupa semen dan tanah yang ditumbuhi vegetasi. Kondisi ini dikhawatirkan
menjadi tempat hidup dan berkembangnya bibit penyakit. Terkait dengan aspek
kenyamanan, ukuran tempat tidur owa jawa di JGC sama seperti ukuran tempat
tidur siamang di PPS Tegal Alur, yaitu masih tergolong kecil dan belum sesuai
dengan yang direkomendasikan oleh Campbell (2008), yakni 1,6 m (p) x 2,0 m (l)
x 2,4 m (t). Pada penelitian Mahardika (2008), kondisi kandang owa jawa di PPS
Gadog memiliki sistem perkandangan yang hampir menyerupai dengan PPS Tegal
Alur, yaitu kandang setengah tertutup, berbentuk rumah panggung dan kotak
pakan yang berukuran 30 cm2. Dalam hal penyediaan air, pihak PPS Gadog
menyediakan tempat minum yang terbuat dari bahan aluminium berbentuk bulat
berdiameter 15 cm. Tempat minum tersebut telah mendukung primata dalam
melakukan aktivitas minumnya di alam. Pada siamang sendiri, aktivitas minum
22
dilakukan dengan cara mendulang air dengan telapak tangan dari lubang batang
pohon, kemudian dialirkan ke dalam mulut sambil menjilati tangannya (Rosyid,
2007).
4.1.2. Kondisi Satwa
Populasi siamang di PPS Tegal Alur sebanyak 7 ekor, yang terdiri dari 6
ekor jantan dan 1 ekor betina. Siamang yang digunakan dalam penelitian ini
sebanyak 6 ekor, yaitu 5 ekor siamang dewasa jenis kelamin jantan (Sapri, Pixy,
Gigih, Mency & Patrick) dan 1 ekor siamang dewasa jenis kelamin betina (Noni).
Terdapat beberapa siamang yang sedang menderita penyakit diare dan masih
dalam kondisi penyembuhan. Kondisi siamang yang dijadikan objek penelitian
ialah siamang yang sehat dan sudah berumur lebih dari 6 tahun. Kondisi siamang
yang sehat mengurangi kekhawatiran adanya penularan pada peneliti dan
memudahkan peneliti dalam melihat aktivitas hariannya. Sehatnya siamang dapat
ditandai dengan normalnya aktivitas hariannya, yaitu siamang akan makan saat
merasa lapar, minum saat merasa haus, melakukan urinasi saat ingin urinasi dan
sebagainya.
Beberapa persyaratan yang dibutuhkan dalam pemeliharaan primata antara
lain kualitas kandang yang baik, layanan dokter hewan spesialis, pengayaan
lingkungan dan berbagai macam makanan dan suplemen (NIDirect, 2014a). Salah
satu upaya yang dilakukan pengelola PPS dalam menjaga kesejahteraan siamang
ialah dengan memperhatikan kondisi satwa dengan adanya pengecekan rutin
setiap hari (daily check-up) dan 2 kali setahun (periodic check-up) oleh dokter
hewan dan penjaga (keeper). Daily check-up dilakukan dengan pemantauan satwa
pada pagi dan sore hari, sedangkan periodic check-up dilakukan dengan adanya
pengukuran kesehatan siamang secara fisik, analisis feses maupun pengecekan
darah. Menurut NIDirect (2014), primata pintar dalam menyembunyikan tanda
fisik. Oleh karena itu mengenali kondisi fisik yang baik dan perilaku normal
ketika sehat akan membantu menemukan tanda-tanda awal adanya perilaku yang
abnormal yang memperburuk kesehatan fisik, sehingga tindakan yang diperlukan
dapat diambil.
23
Aspek kesehatan satwa menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam
penelitian Yohanna et al. (2014) terhadap owa jawa yang merupakan satu
keluarga dengan siamang di Javan Gibbon Center (JGC). Setidaknya aspek-aspek
pengelolaan kesehatan owa jawa yang diperhatikan antara lain, aspek pemeriksaan
feses, luka, vaksinasi, kebersihan kandang dan pencegahan penularan penyakit
pada pengelola satwa. Pihak JGC tidak menjadwalkan secara rutin mengenai
pengecekan feses owa jawa, namun disebutkan beberapa owa sudah diketahui
kondisi kesehatannya melalui feses. Menurut Campbell (2008), setidaknya
pemeriksaan feses pada primata harus dilakukan dua kali dalam setahun dan harus
dilaksanakan ke dalam prosedur karantina rutin. Hal ini telah sesuai dengan apa
yang dilakukan pengelola PPS Tegal Alur dalam memasukan pemeriksaan feses
pada periodic check-up. Penelitian lain yang dilakukan oleh Akbar (2011) di PPS
Cikananga menjelaskan bahwa sebelum dikarantina setiap satwa termasuk
primata, akan dilakukan pengecekan kesehatan terlebih dahulu untuk mengetahui
kondisi fisik dan kesehatan satwa, meliputi penimbangan bobot tubuh,
pengukuran panjang atau tinggi tubuh dan pengecekan penampilan fisik. Hal
tersebut dilakukan untuk mengetahui penilaian awal dalam membuat keputusan
pelepasliaran.
4.2. Manajemen Pakan
4.2.1. Waktu dan Cara Pemberian Pakan
Pakan utama siamang di PPS Tegal Alur diberikan sebanyak tiga kali
sehari setiap pukul 07.00 WIB, 13.00 WIB dan 15.00 WIB. Pemberian pakan oleh
pengelola PPS telah sesuai dengan waktu pemberian pakan siamang di
International Center for Gibbon Studies, California sebanyak tiga kali dalam
sehari, yaitu sekitar pukul 07.00, 10.30 dan 14.30 (Mootnick, 1997). Pemberian
pakan tersebut memang sudah sepatutnya mengacu pada aktivitas makan siamang
di habitat alaminya (Sibarani, 2012). NIDirect (2014) menambahkan, primata
harus diberi makan sebanyak tiga kali untuk mengurangi kebosanan dan masalah
pada lambung. Hal yang dilakukan keeper sebelum pemberian pakan antara lain
dilakukan pencucian dan pemotongan pakan terlebih dahulu dengan tidak dibuang
24
bagian kulit dan bijinya, kemudian keeper meletakkan pakan yang siap diberikan
ke siamang di tempat pakan permanen.
Pemasokan pakan satwa di PPS dilakukan dua kali sehari dengan variasi
pakan yang beragam. Semua pasokan pakan untuk satwa diletakkan di dapur
pakan dan kotak penyimpanan untuk pakan jenis daging. Penyediaan air dalam
botol minum hanya dilakukan pada individu siamang betina dengan diberikan
secara ad libitum sehingga air selalu tersedia. Pakan siamang di pagi dan siang
hari diberikan di tempat pakan permanen tepat di depan kandang, sedangkan
pakan di sore hari diletakkan di atas kandang berupa dedaunan. Pemberian pakan
yang diletakkan di atas kandang telah mendukung siamang untuk melakukan
aktivitas makannya seperti di habitat alaminya, sedangkan letak tempat pakan
permanen yang posisinya di bawah kandang terkadang membuat siamang tidak
melakukan aktivitas makan sesuai dengan perilaku di alamnya. Menurut Rosyid,
(2007) sebagai satwa arboreal, siamang melakukan aktivitas makannya di atas
pohon.
Dalam menjamin kebebasan berperilaku alami, pengelola PPS perlu
menyediakan media khusus pemberian pakan di bagian atas kandang melihat
tempat pakan kandang yang permanen. Seperti tempat pakan khusus dari wadah
plastik yang digantung pada ketinggian ½ - ¾ kali dari tinggi kandang, namun
harus tetap disesuaikan dengan jangkauan keeper. Peletakan tempat pakan yang
tidak mendukung siamang dalam melakukan aktivitas alaminya, belum memenuhi
prinsip kesejahteraan apalagi ditunjukkan dengan perilaku abnormal, yakni
perilaku yang sering berada di lantai kandang, baik saat makan, bergerak maupun
tidur, karena secara alami siamang selalu berada di bagian atas kandang atau atas
pohon.
4.2.2. Pakan Siamang
Pakan siamang dibagi menjadi pakan utama dan pakan tambahan. Pakan
utama berupa buah dan sayur, sedangkan pakan tambahan berupa dedaunan
(Lampiran 1). Siamang juga diberikan vitamin seminggu sekali untuk memenuhi
kebutuhan nutrisinya. Pakan yang diberikan terdiri dari 12 jenis, dengan jenis
buah-buahan lebih banyak dibanding jenis sayur dan dedaunan (Tabel 4). Hal ini
25
disebabkan karena siamang adalah satwa frugivorous dan kemungkinan besar
sangat berperan dalam proses pemencaran biji di habitat alaminya (Santosa et al.,
2010). Pemberian pakan berupa dedaunan yaitu daun pepaya (Carica papaya)
dilakukan pada sore hari. Terkadang terlihat siamang jantan dan betina memakan
serangga-serangga kecil di sekitar dinding kandang, seperti laba-laba dinding
(Parasteatoda sp.). Hal ini telah sesuai karena memang primata pada umumnya
merupakan tipikal omnivora (Dunbar & Cowlishaw, 2000).
Tabel 4. Jenis pakan siamang di PPS Tegal Alur
Kelompok Nama lokal Nama ilmiah
Buah Pepaya Carica papaya Jeruk Citrus sinensis Semangka Citrullus lanatus
Timun Cucumis sativus Pisang lampung Musa paradisiaca Pisang kepok Musa cuminata balbisiana Jambu biji Psidium guajava Salak Salacca zalacca
Kacang panjang Vigna unguiculata ssp.
Sayur Sawi Brassica chinensis Wortel Daucus corota
Dedaunan Daun pepaya Carica papaya
Jenis pakan siamang di setiap tempat konservasi berbeda-beda. Taman
Satwa Taru Jurug memberikan jenis pakan siamang meliputi pisang, nanas,
pepaya, timun, bengkuang, apel, melon, semangka, jeruk, jagung rebus, wortel,
kacang panjang, tempe rebus dan telur ayam rebus (Sharafina, 2017).
International Center for Gibbon Studies memberikan siamang pakan berupa apel,
bayam, brokoli, kiwi, seledri, ubi jalar, pisang dan selada (Mootnick, 1997).
4.2.3. Palatabilitas Pakan
Pemilihan jenis pakan merupakan awal dimulainya aktivitas makan
siamang karena pengelola PPS memberikan jenis pakan yang cukup bervariasi.
Menurut Church (1976), sifat seleksi yang dimiliki hewan cukup tinggi terhadap
pakan yang tersedia. Siamang merupakan primata yang sangat selektif dalam
memilih pakan. Pakan yang disukai siamang akan diambil terlebih dahulu,
kemudian memakannya sampai habis. Pakan yang tidak disukai akan diambil
terakhir kali dan tidak dihabiskan atau dibuang. Berdasarkan peringkat
26
palatabilitas pakan, siamang di PPS Tegal Alur sangat menyukai pisang lampung
kemudian dilanjutkan buah pepaya dan salak, sedangkan semangka berada pada
tingkat kesukaan paling akhir (Tabel 5). Pakan yang diberikan pada pagi dan sore
sebagian besar dihabiskan oleh siamang. Terkadang sisa pakan yang jatuh
dibawah kandang, diambil oleh siamang kemudian dikonsumsi kembali.
Tabel 5. Palatabilitas pakan siamang di PPS Tegal Alur
Jenis pakan Tingkat
palatabilitas
Nama lokal Nama ilmiah
Pisang lampung Musa paradisiaca 1
Pisang kepok Musa cuminata balbisiana 4
Sawi Brassica chinensis 5
Timun Cucumis sativus 9
Salak Salacca zalacca 3
Wortel Daucus corota 6
Jeruk Citrus sinensis 7
Kacang panjang Vigna unguiculata ssp. 10
Pepaya Carica papaya 2
Jambu Psidium guajava 8
Semangka Citrullus lanatus 11
Keterangan : Angka 1 sampai 11 menunjukkan nomor urutan pemilihan pakan
yang pertama sampai yang terkahir kali dikonsumsi
Urutan pemilihan pakan merupakan salah satu bentuk pendekatan untuk
mengetahui tingkat kesukaan pakan yang diberikan. Dengan mengetahui pakan
kesukaan siamang, memudahkan keeper dan dokter hewan untuk melakukan
variasi pakan setiap harinya dan modifikasi pakan saat siamang sakit. Tingkat
pakan yang sangat disukai siamang akan diberikan secara jarang. Hal ini bertujuan
untuk memudahkan pemberian pakan pada siamang yang sakit. Umumnya
siamang yang sakit akan mengalami nafsu makan yang menurun, sehingga dengan
diberikannya pakan yang sangat disukai ditambah dengan vitamin, diharapkan
siamang memilih pakan tersebut, kemudian memakannya. Hal ini dapat
memudahkan fase penyembuhannya.
Secara umum siamang di lokasi penelitian terlihat menyukai buah-buahan
yang sudah matang, kemudian dilanjutkan dengan jenis sayur-sayuran. Tingkat
palatabilitas pakan dipengaruhi oleh tekstur, aroma, warna dan rasa dari pakan
yang diberikan. Berdasarkan pengamatan, buah yang disukai siamang memiliki
27
warna dan rasa yang beragam seperti jenis pisang dan pepaya. Hal ini sesuai
dengan Rosyid (2007), bahwa pakan utama yang disukai oleh siamang di alam
berupa buah-buahan yang masak. Buah yang dihabiskan siamang umumnya
memiliki warna yang menarik dan rasa yang cukup enak, manis, asam dan sepah
(Atmanto et al., 2014).
Pisang merupakan jenis pakan yang paling disukai siamang diantara pakan
yang diberikan. Hal ini diduga karena pisang memiliki warna yang menarik,
aroma yang khas dan tekstur yang lunak sehingga mudah dicerna oleh sistem
pencernaan siamang. Di habitat aslinya pisang juga mudah didapat. Pengelola
biasanya menggunakan pisang sebagai media tempat pemberian vitamin setiap
minggunya. Hasil serupa juga dialami oleh Sharafina (2017) bahwa siamang di
Taman Satwa Taru Jurug juga menempatkan pisang sebagai pakan yang paling
disukai siamang. Palatabilitas pakan tiap siamang yang berbeda diduga karena
perbedaan pola makan terdahulu, kondisi lingkungan kandang, fisiologis dan
aktivitas hariannya.
4.2.4. Jumlah Konsumsi Pakan
Pakan yang disukai siamang dapat ditentukan juga dengan mengetahui
palatabilitas pakannya dengan menghitung jumlah konsumsi pakan hariannya.
Tabel jenis pakan yang direkomendasikan pengelola sudah terdapat di dapur
pakan, namun jumlah pakan yang diberikan oleh keeper setiap harinya berbeda
karena biasanya tidak ditimbang terlebih dahulu. Pemberian pakan hanya
berdasarkan estimasi kebutuhan pakan tiap individu. Berikut merupakan tabel
rata-rata jumlah pakan yang diberikan dan dikonsumsi selama penelitian 14 hari
(Tabel 6).
Siamang di PPS Tegal Alur mengonsumsi rata-rata 559.63 g setiap hari
dengan sisa pakan berkisar 21.86 g (Tabel 6). Selama pengamatan konsumsi
pakan individu-individu siamang jantan lebih banyak dibanding siamang betina.
Secara umum siamang jantan memang mengkonsumsi lebih banyak pakan
dibanding siamang betina (Masy’ud & Ginoga, 2016). Seluruh siamang memiliki
nafsu makan yang cukup tinggi ditandai dengan nilai rata-rata persentase
konsumsi di atas 90%. Nafsu makan yang tinggi menunjukkan adanya kesehatan
28
yang baik pada siamang, karena menurut Masy’ud & Ginoga (2016), kondisi
kesehatan satwa dipengaruhi oleh jumlah konsumsi pakan.
Tabel 6. Rata-rata jumlah pakan yang diberikan dan konsumsi siamang setiap hari
Hari ke- Jumlah yang
diberikan (g) Sisa (g)
Jumlah yang
dikonsumsi (g)
Persentase
konsumsi (%)
1 524,67 17,83 507,83 96,79
2 532,50 24,83 506,67 95,15
3 573,67 19,50 553,67 96,51
4 622,00 25,50 596,33 95,87
5 527,17 13,33 513,17 97,34
6 535,67 16,17 522,00 97,45
7 705,00 23,17 681,83 96,71
8 621,17 13,83 607,33 97,77
9 481,50 19,33 462,17 95,98
10 571,83 36,50 535,33 93,62
11 519,50 22,33 497,17 95,70
12 503,50 13,83 489,67 97,25
13 699,17 32,33 666,83 95,38
14 722,33 27,50 694,83 96,19
Jumlah 8139,67 306,00 7834,83 1347,73
Rata-rata 581,40 21,86 559,63 96,27
Standar deviasi 76.99 6.78 73.93 1.03
Berdasarkan bobot tubuh siamang di PPS Alur yang berkisar antara 4 – 6
kg, maka jumlah konsumsi makan sudah memenuhi minimal 10% dari bobot
tubuhnya, yaitu sebesar 400 g – 600 g. Menurut Elly et al. (2013), kebutuhan
pakan hewan ternak 10% dari bobot badannya. Alikodra (1990) menambahkan,
tingkat konsumsi pakan satwa liar dapat ditentukan dari nilai bobot tubuhnya yang
membutuhkan makanan sekitar 10%-20% bobot tubuhnya setiap hari.
4.3. Status Gizi
4.3.1. Ciri fisik dan Antropometri
Kondisi fisik siamang menggambarkan keadaan tubuh siamang yang
tampak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kesehatan siamang juga dapat
ditandai dengan kondisi fisik yang normal. Menurut Bennett et al. (1995),
kesehatan fisik merupakan langkah paling mudah untuk menilai kesejahteraan
umum primata. Dalam menunjang kesejahteraannya, sejatinya primata harus
bebas dari ketidaknyamanan fisik dan rasa sakit yang dialami. Ukuran dimensi
tubuh primata juga dapat menunjukkan status gizinya dengan mengetahui ukuran
29
tubuh normalnya. Data fisik dan postur tubuh siamang selama pengamatan
disajikan pada Tabel 7.
Berdasarkan hasil pengamatan, siamang di PPS Tegal Alur berumur
sekitar 7 – 9 tahun. Individu-individu jantan memiliki bobot tubuh lebih berat
dibanding individu betina. Menurut Napier (1967), secara fisik memang bobot
tubuh siamang jantan lebih besar dibandingkan dengan betina. Umur seluruh
siamang sudah menunjukkan kelompok dewasa (adult) pada fase pertumbuhannya
menurut Santosa et al. (2010), yaitu fase pertumbuhan siamang dimulai dari bayi
saat lahir sampai berumur 2-3 tahun, kemudian anak (juvenile-1) saat berumur
kira-kira 2-4 tahun, muda (juvenile-2) saat berumur kira-kira 4-6 tahun, sub-
dewasa (sub-adult) saat mulai umur 6 tahun, dan dewasa (adult) melebihi umur 6
tahun.
(A) (B) (C) (D) (E)
Gambar 6. Postur tubuh siamang betina berdiri hadap belakang (tangan & kaki
bergetar) (A), duduk (B), rebahan (C), postur tubuh siamang jantan
berdiri hadap depan (D) dan duduk (E)
Bobot tubuh siamang di PPS Tegal Alur berkisar antara 5 - 6 kg. Standar
antropometri penilaian status gizi primata saat ini belum ada, oleh karena itu
dilakukan pendekatan dengan membandingkan bobot tubuh dan tinggi siamang
berdasarkan literatur. Beberapa siamang di alam diketahui bahwa jantan dewasa
memiliki bobot rata-rata 11,9 kg sedangkan betina 10,7 kg (Kuswanda et al.,
2019). Hasil survei di penangkaran, bobot rata-rata jantan dewasa sebesar 12,8 kg
dan betina sebesar 10,5 kg (Gron, 2008). Bobot tubuh siamang di lokasi penelitian
memiliki perbedaan sekitar 5 – 6 kg dibandingkan dengan sampel di alam dan di
penangkaran.
30
Tabel 7. Hasil pengamatan ciri fisik dan antropometri siamang di PPS Tegal Alur
Data fisik dan
postur
Siamang Standar normal kesehatan
siamang Noni ♀ Sapri ♂ Pixy ♂ Gigih ♂ Mency ♂ Patrick ♂
Tahun
penempatan 2017 2016 2009 2009 2009 2016
Dewasa (adult) : > 6 tahun [7]
Umur (tahun) 9 7 7 8 8 7
Antropometri
Tinggi (cm) 90 110 85 100 90 85 100 cm [2]
80 – 90 cm [3]
Bobot tubuh
(kg) 5 6 5 6 6 5,5
Jantan dewasa min 6,8 kg, max
19,4 kg; betina dewasa min 6,8
kg, max 15,7 kg [1]
Di alam : jantan dewasa (11,9
kg), betina dewasa (10,7 kg) [2]
Di penangkaran : jantan dewasa
(12,8 kg), betina dewasa (10,5
kg) [3]
Ciri fisik
Mata Sklera coklat, iris
hitam kecoklatan
Sklera coklat, iris
hitam kecoklatan
Sklera coklat, iris
hitam kecoklatan
Sklera coklat, iris
hitam kecoklatan
Sklera coklat, iris
hitam kecoklatan
Sklera coklat, iris
hitam kecoklatan
Sebagian besar primata memiliki
warna skrela coklat atau hitam [6]
Gigi Putih & lengkap Putih & lengkap Putih & lengkap Lengkap, kusam Putih & lengkap Putih & lengkap Susunan gigi 2/2, 1/1. 2/2, 3/3 :
32 [4]
Rambut
Hitam,
depigmentasi,
rontok dan jarang
Hitam, lebat Hitam, depigmentasi Hitam, lebat Hitam, lebat Hitam, lebat
Rambut tubuh : hitam pekat
mengkilap; Rambut wajah :
kecokelatan [3]
Bekas luka - -
Pada kepala, tangan
kiri, kaki kiri,
pinggul kanan
- Pada sebelah mata
kanan
Pada sebelah mata
kanan Tidak ditemukan bekas luka [5]
Postur tubuh
abnormal
Istirahat - - - - - - Tangan, kaki dan jari-jari yang
panjang memungkinkan siamang
menjangkau sel-sel kandang
untuk melakukan pergerakan
berayun secara bebas di alam /
kandang [5]
Brakiasi Gemetar pada kaki
dan tangan - - - - -
Bergerak Gemetar pada kaki
dan tangan - - - - -
Keterangan : 1. NRC (2003); 2. Kuswanda et al., (2019) ; 3. Gron (2008); 4. Myers et al., (2000); 5. Nidirect.gov (2020), 6. Than (2006), 7. Santosa et
al., (2010)
31
Pengamatan secara langsung memang menunjukkan bahwa kondisi
siamang memiliki badan yang kurus, terutama pada siamang betina. Hal ini bisa
menjadi perhatian khusus bagi pengelola untuk memperhatikan asupan gizi dan
pengecekan secara rutin apakah ada penyakit tertentu yang membuat kondisi
siamang belum sesuai dengan rata-rata bobot tubuh di alam ataupun di
penangkaran. Data tinggi tubuh seluruh siamang sudah menunjukkan rata-rata
tinggi siamang normal yaitu mencapai 1 m. Menurut Kuswanda et al. (2019),
tinggi siamang dapat mencapai 1 meter dengan bobot mencapai 14 kg.
(A) (B) (C)
Gambar 7. Kondisi rambut siamang betina yang rontok (Noni) (A), jantan yang
mengalami depigmentasi (Pixy) (B) dan jantan yang lebat (Sapri) (C)
di PPS Tegal Alur
Perawatan diri adalah perilaku normal primata yang ditandai dengan
melakukan aktivitas membersihkan diri seperti menggaruk dan menjilat rambut.
Perawatan diri yang berlebihan hingga menimbulkan stres, mampu membuat
rambut primata rontok dan menimbulkan luka pada kulit. Warna rambut yang
hitam lebat merupakan ciri siamang sehat dan normal. Rambut siamang berwarna
hitam dan sedikit abu-abu gelap di bagian antara dagu dan mulutnya (Palombit,
1997). Berdasarkan pernyataan tersebut, Sapri, Gigih, Mency dan Patrick
menunjukkan kondisi rambut yang normal, sedangkan Noni dan Pixy memiliki
kondisi rambut yang sedikit berbeda, yaitu mengalami depigmentasi dan rontok
(Gambar 7). Rambut yang rontok dapat mengurangi fungsi dari rambut itu sendiri,
yaitu sebagai pelindung dari serangan luar dan penghangat tubuh. Siamang
dengan rambut yang rontok dan mengalami depigmentasi dikhawatirkan berada
dalam kondisi stres atau memiliki penyakit tertentu seperti achromotrichia.
Menurut NRC (2003), achromotrichia pada beberapa jenis mamalia disebabkan
karena kelebihan unsur Zink, sehingga menyebabkan defisiensi Cu. Mann (1968)
32
menambahkan, rambut rontok pada monyet capuchin (Cebus albifron) disebabkan
karena kekurangan vitamin B6.
Gambar 8. Morfologi gigi siamang jantan di PPS Tegal Alur dengan susunan gigi
lengkap dan bersih
Semua primata patut memiliki kesehatan gigi dan mulut yang baik.
Menurut NIDirect (2014), masalah dengan kesehatan mulut dan kerusakan gigi
pada umumnya terjadi pada primata tawanan, terutama sebagai akibat dari diet
yang tidak tepat. Pengamatan secara morfologi menunjukkan bahwa siamang di
PPS Tegal Alur memiliki susunan gigi yang lengkap dan terlihat bersih, yaitu
berjumlah 32. Siamang memiliki susunan gigi 2/2, 1/1, 2/2, 3/3 = 32 (Myers et al.,
2000) dengan fungsi dasarnya yaitu mengumpulkan dan mengunyah makanan
(Karyawati, 2012). Selain itu mata yang sehat menjadi salah satu tanda kesehatan
fisik pada primata. Penglihatan yang sehat pada mata siamang di lokasi penelitian
ditandai dengan adanya respons mata saat ada pergerakan di depan kandang,
seperti lewatnya keeper atau peneliti. Berdasarkan pengamatan morfologi, mata
seluruh siamang memiliki sklera berwarna coklat dan iris berwarna hitam
kecokelatan. Hal ini sesuai dengan Than (2006), bahwa sebagian besar primata
memiliki warna skrela berwarna coklat atau hitam seragam, sehingga cukup sulit
menentukan arah yang mereka lihat dari mata mereka sendiri.
33
(A) (B) (C)
(D) (E) (F)
Gambar 9. Morfologi mata siamang betina (Noni) (A), jantan 1 (Sapri) (B), jantan
2 (Gigih) (C), jantan 3 (Mency) (D), jantan 4 (Pixy) (E) dan jantan 5
(Patrick) (F) di PPS Tegal Alur
Ketidaknyamanan fisik pada primata dapat dilihat dari tanda-tanda yang
tidak normal, seperti kehilangan nafsu makan, tidak responsif, melukai diri sendiri
dan postur tubuh yang tidak biasa. Hasil pada Tabel 9 menunjukkan bahwa
terdapat postur tubuh yang tidak biasa pada siamang betina (Noni). Selama
pengamatan teramati postur tubuh Noni saat makan, bergelantung dan berdiri
menunjukkan kaki dan tangan yang bergetar (Gambar 6). Kondisi yang dialami
Noni diduga karena umurnya yang sudah tua dan penempatan yang lama di PPS
Tegal Alur. Struktur tangan, kaki dan jari-jari yang panjang seharusnya
memungkinkan siamang untuk menjangkau sel-sel kandang untuk melakukan
pergerakan berayun seperti apa yang dilakukan di tajuk-tajuk pohon (NIDirect,
2014a). Lanjutnya, primata yang menua dan mengalami gangguan pada
pergerakannya mungkin menderita penyakit artritis atau akibat dari umur yang
sudah menua (NIDirect, 2014a). Hal ini perlu diperhatikan pengelola PPS untuk
menghindari ketidaknyamanan dan rasa sakit pada primata yang merupakan
bagian dari kesejahteraan satwa.
4.3.2. Konsumsi Nutrisi Pakan
Kebutuhan nutrisi merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam
menunjang kesejahteraan siamang. Nutrisi yang diperoleh digunakan siamang
dalam upaya mendapatkan energi dan kebutuhan gizi lainnya seperti protein,
lemak, karbohidrat dan air. Gizi tersebut berguna untuk melakukan aktivitas dan
fisiologis tubuhnya. Menurut Kurniawaty (2009), jumlah konsumsi pakan dan
34
kandungan zat makanan tiap bahan pakan mempengaruhi nutrisi pakan yang
dikonsumsi siamang. Rasmada (2008) menambahkan, kandungan nutrisi pakan
sejalan dengan peningkatan konsumsi pakan pada satwa. Kandungan nutrisi tiap
jenis pakan berbeda-beda disajikan pada Lampiran 8.
Informasi pada Lampiran 8 menunjukkan bahwa kedua jenis pisang
mengandung karbohidrat paling tinggi, kemudian dilanjutkan dengan semangka.
Pisang mengandung banyak pati sehingga mudah dirombak tubuh untuk menjadi
sumber energi utama bagi siamang. Kebutuhan energi ini dibutuhkan siamang
untuk melakukan aktivitas hariannya. Menurut Rahman (2011), energi pada pakan
dikatakan terlalu tinggi jika lebih dari 3000 kal/g. Kandungan energi untuk semua
jenis pakan menunjukkan angka yang rendah, yaitu di bawah 3000 kal/g.
Cuaca di Jakarta pada periode April - Juni 2020 tergolong panas dan
memiliki curah hujan yang rendah, yakni 0-20 mm (BMKG, 2020). Kondisi
tersebut membuat siamang di PPS Tegal Alur membutuhkan lebih banyak air
untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuhnya. Siamang memperoleh
kebutuhan air dengan mengkonsumsi pakan berupa semangka, sawi dan pepaya.
Semangka diketahui sebagai buah yang bersifat dingin, penyejuk tubuh dan
penghilang haus (Safuan, 2007). Menurut NRC (2003), kebutuhan air pada
primata beragam, tergantung komposisi pakan, metabolisme tubuh dan aktivitas
hariannya.
Tabel 8. Konsumsi gizi pakan siamang di PPS Tegal Alur
Individu
Zat Gizi
Energi
(kal/g/h)
Protein
(g/bb/h)
Lemak
(g/bb/h)
Karbohidrat
(g/bb/h)
Air
(g/bb/h)
Noni 356,99 9,32 2,14 85,10 517,45
Sapri 384,49 9,66 2,19 141,31 553,04
Pixy 375,75 9,03 1,83 149,01 421,14
Gigih 309,84 7,35 1,56 137,04 357,98
Mency 389,99 8,42 1,70 184,00 431,53
Patrick 391,51 8,50 1,73 180,46 427,57
Jumlah 2208,57 44,02 11,74 1994,72 2304,76
Rata-rata 368,09 7,34 1,96 332,45 384,13
Berdasarkan hasil perhitungan konsumsi gizi, rata-rata siamang di PPS
Tegal Alur memperoleh zat gizi berupa energi sebesar 368,09 kal/g/h, protein
sebesar 7,34 g/bb/h, lemak sebesar 1,96 g/bb/h, karbohidrat sebesar 332,45 g/bb/h
35
dan air sebesar 384,13 g/bb/h (Tabel 8). Perbedaan konsumsi gizi tiap siamang
yang tidak jauh berbeda disebabkan karena selama pengamatan seluruh siamang
dalam keadaan sehat sehingga memiliki nafsu makan yang tinggi. Namun tetap
perlu diperhatikan konsumsi gizi tiap individu karena tidak semua satwa bereaksi
terhadap pemberian pakan yang sama. Menurut NIDirect (2014b), salah satu
langkah untuk memantau asupan makanan tiap individu adalah memastikan
palatabilitas pakan yang disukai (seperti pisang), tidak mengarah pada perilaku
makan yang tidak seimbang.
Standar kebutuhan energi, protein, lemak dan karbohidrat pada siamang
belum tersedia, oleh karena itu dilakukan pendekatan pada kebutuhan energi
monyet ekor panjang dewasa, yaitu sebesar 100-210 kal/bb/h, kebutuhan protein
primata dewasa sebesar 3 g/bb/ h dan kebutuhan lemak Trachypitecus cristatus
sebesar 9,17 g/bb/h (NRC, 2003). Berdasarkan informasi tersebut, kebutuhan
energi siamang di PPS Tegal Alur melebihi standar dari NRC (2003) untuk
ukuran monyet ekor panjang dewasa yang umumnya memiliki berat 3 - 4 kg pada
betina dan 5 -7 kg pada jantan (Payne et al., 2000). Jika dibandingkan dengan
ukuran bobot tubuh siamang dewasa yang berkisar 10 – 12 kg, maka dapat
diasumsikan kebutuhan energi seluruh siamang sudah mendekati standar normal.
Konsumsi protein seluruh siamang melebihi kebutuhan protein primata dewasa
yang direkomendasikan NRC (2003), yaitu memiliki rata-rata sebesar 7,34 g/bb/h.
Kebutuhan konsumsi lemak juga menunjukkan adanya kekurangan dari jumlah
yang direkomendasikan oleh NRC (2003).
Kekurangan konsumsi lemak disebabkan karena pemberian berlebih pada
pakan yang mengandung protein tinggi. Protein yang tinggi pada pakan
disebabkan oleh pemberian berlebih daun pepaya yang memiliki kadar protein
sebanyak 8 g kandungan gizi per 100 gram pakan. Pengelola melakukan
pemberian daun pepaya dengan tujuan melancarkan sistem pencernaan siamang.
Diketahui memang daun pepaya mengandung serat kasar tinggi dan enzim papain
sehingga dapat melancarkan defekasi. Namun perlu adanya batasan pemberian
daun pepaya karena memiliki kadar protein yang tinggi. Menurut Burek et al.
(1988), walaupun kelebihan protein patologis pada jenis monyet jarang terjadi,
namun kasus ini memungkinkan adanya perubahan patologis di ginjal yang
36
kadang menyebabkan gagal ginjal terminal. Pemberian pakan berupa daun pepaya
harus dikurangi dan digantikan dengan pemberian pakan alternatif berupa buah
yang mengandung lemak tinggi, seperti alpukat atau sawo tiap harinya. Sharafina
(2017) dalam penelitiannya merekomendasikan pemberian jagung rebus sebagai
pakan pengganti tempe sebagai sumber energi dan lemak.
4.4. Perilaku Harian
Pengamatan perilaku harian siamang di PPS Tegal Alur dilakukan pada
pukul 07.00 WIB - 16.00 WIB, selama 126 jam. Pengamatan dilakukan pada
waktu aktif siamang yaitu pada siang hari. Menurut Mubarok (2012), aktivitas
harian yang dilakukan oleh kelompok Hylobatidae di tajuk pohon dimulai dari
sebelum matahari terbit hingga sore hari. Aktivitas yang diamati dikelompokkan
menjadi dua golongan aktivitas, yaitu aktivitas yang berhubungan langsung
dengan pola makan, meliputi aktivitas makan, minum, urinasi dan defekasi,
kemudian aktivitas yang tidak berhubungan langsung dengan pola makan meliputi
aktivitas grooming, bergerak dan istirahat. Persentase aktivitas siamang di PPS
Tegal Alur disajikan pada Gambar 10.
14.68
1.09 1.48 0.99
17.14
21.42
43.21
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
Makan Minum Urinasi Defakasi Grooming Bergerak Istirahat
% A
ktiv
itas
Jenis Aktivitas
Gambar 10. Rata-rata persentase aktivitas harian siamang di PPS Tegal Alur
4.4.1. Perilaku yang berhubungan langsung dengan pola makan
Perilaku yang berhubungan langsung dengan pola makan, yaitu aktivitas
makan, minum, defekasi dan urinasi. Aktivitas makan menempati urutan paling
37
tinggi pada perilaku pola makan itu sendiri, yaitu memiliki rata-rata persentase
sebesar 14,68 %, kemudian diikuti dengan aktivitas urinasi sebesar 1,48 %,
aktivitas minum sebesar 1,09% dan aktivitas defekasi sebesar 0,99% (Gambar
10).
Aktivitas makan merupakan salah satu perilaku harian siamang. Menurut
Alikodra (1990), aktivitas makan dijadikan sebagai kebutuhan energi untuk
melakukan aktivitas harian dan menjaga kelangsungan hidup siamang. Aktivitas
makan siamang berturut-turut dimulai dari pemilihan pakan, kemudian
mengambil pakan, memeriksa pakan, mengolah pakan, menggigit pakan,
mengunyah pakan, menelan pakan, mengeluarkan pakan, sampai membuang
pakan. Terkadang terlihat juga siamang mengambil pakan yang telah dibuang
untuk diolah dan dikonsumsi kembali.
(A) (B)
Gambar 11. Aktivitas makan siamang betina (A) dan jantan (B) di PPS Tegal Alur
Aktivitas makan menempati urutan keempat dalam rata-rata persentase
aktivitas harian siamang di PPS Tegal Alur. Setiap siamang memiliki persentase
aktivitas makan yang berbeda-beda. Perbedaan aktivitas makan tiap siamang
disebabkan karena adanya perbedaan cara menghabiskan pakannya. Contohnya
saat pemberian pakan siamang betina (Noni) dan dua individu siamang jantan
(Pixy & Gigih), mereka langsung menghabiskan pakan saat itu juga, sedangkan
individu-individu lainnya tidak langsung menghabiskan pakanannya saat itu,
tetapi berangsur-angsur sambil melakukan aktivitas lokomosi dan grooming.
Setelah mengambil pakan pertamanya, biasanya beberapa siamang bergerak ke
bagian atas kandang kemudian menghabiskan waktu makannya di atas kandang,
seperti di tempat istirahatnya atau di sel kandang bagian atas (Gambar 11).
38
Hal ini sejalan dengan Rosyid (2007) yang mengatakan bahwa posisi
siamang saat makan biasanya duduk atau berdiri dan dapat pula menggantung di
cabang pohon. Lain halnya dengan siamang betina (Noni) yang kebanyakan
menghabiskan waktu untuk makan dilantai kandang. Sebagai satwa arboreal,
sudah sepatutnya siamang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk makan
dan bergerak di bagian atas kandang untuk membiasakan pada perilaku alaminya.
Berdasarkan pengamatan, alasan Noni tidak melakukan aktivitas makannya di atas
kandang karena ukuran kandang yang terlalu kecil sehingga sangat membatasi
pergerakannya. Pihak PPS perlu memberikan perhatian khusus pada Noni untuk
terbiasa kembali pada perilaku alaminya dalam upaya persiapan pelepasliaran ke
alam atau ke lembaga konservasi. Terlihat selama pengamatan siamang
melakukan aktivitas makannya dengan cara duduk di atas kandang, batang kayu
atau tempat istirahatnya. Hal ini sesuai dengan penelitian Sharafina (2017), bahwa
aktivitas makan siamang di Taman Satwa Taru Jurug kebanyakan dilakukan
dengan cara duduk di batang kayu. Siamang di habitat alaminya memerlukan
vegetasi yang saling terhubung antar cabang pohon, karena termasuk satwa
arboreal yang melakukan sebagian besar aktivitasnya ditajuk pohon dan jarang
sekali turun ke lantai hutan (Sultan et al., 2009).
Jumlah pakan yang diberikan pengelola PPS untuk seluruh siamang sama,
sehingga kelimpahan jenis pakan tidak mempengaruhi aktivitas makannya.
Menurut Meijaard et al. (2001), palatabilitas dan kelimpahan jenis pakan mampu
mempengaruhi aktivitas makan siamang. Pakan yang dikonsumsi Sapri umumnya
tidak bersisa. Sisaan pakan yang biasa dijumpai berupa kulit dan biji buah-
buahan. Kulit buah-buahan yang tidak bisa diolah antara lain kulit pisang kepok,
salak, jeruk dan kacang panjang, sedangkan kulit pisang lampung mampu
dihabiskan karena memiliki tekstur lunak dan ketebalan yang tipis. Adanya variasi
tekstur dalam pemberian pakan membantu siamang memanfaatkan gigi-giginya
yang kuat. Diketahui bahwa siamang mempunyai gigi taring yang sama pada
jantan dan betina (Christyanti, 2014), yang berguna untuk mengunyah dan
mencabik makanan.
Siamang memiliki kebiasaan yang unik saat mengkonsumsi pakan yang
diberikan keeper. Saat mengupas kulit, siamang menggunakan kaki untuk
39
mencengkeram buah, kemudian salah satu tangannya mengupas kulit, lalu tangan
dan kaki lainnya mencengkeram sel-sel kandang. Keunikan lainnya ditunjukkan
saat memakan kacang panjang. Siamang menggunakan salah satu tangannya
untuk mencengkeram dan mengelupas kacang panjang, kemudian mengeluarkan
isinya menggunakan gigi serinya. Siamang hanya memakan kacang panjang yang
masih segar dan muda, sedangkan kacang panjang yang sudah tua tidak akan
dimakan. Selain itu siamang suka menjilat sisa makanan yang terdapat pada
tangan atau bagian tubuh mereka. Kulit buah yang biasa dikonsumsi kembali atau
sekedar dijilat, yaitu kulit pisang kepok, kulit jeruk dan kulit salak. Selama
pengamatan, Noni, Mency dan Patrick terlihat selektif dalam memilih pakan. Hal
ini ditandai dengan perilaku mengeluarkan kembali pakan yang kurang disukai
dari mulut. Aktivitas ini umumnya terlihat saat mengkonsumsi jeruk karena hanya
mengambil sari jeruknya saja. Ketika sari jeruk sudah didapat, maka sisanya akan
dikeluarkan dari mulut.
Dalam memenuhi kebutuhan air, pengelola PPS Tegal Alur menyediakan
wadah air berupa botol pada beberapa satwa liar salah satu diantaranya yaitu pada
siamang betina (Noni). Rata-rata persentase aktivitas minum siamang sebesar
1,09% (Gambar 10). Rendahnya persentase minum siamang disebabkan karena
pengelola PPS hanya memberikan minum kepada Noni. Individu-individu
siamang jantan tidak diberikan minum berupa wadah botol berisi air dikarenakan
mereka memiliki tingkah laku yang agresif dan suka memainkan wadah minum
tersebut, sehingga menyebabkan wadah banyak yang hancur. Pihak PPS perlu
memperhatikan pemasangan wadah minum untuk individu-individu siamang
jantan demi menunjang kebutuhan air untuk tubuh mereka. Noni meminum air
dengan cara menyedot air yang tersedia di dalam botol. Cara meminum seperti ini
tidak mencerminkan perilaku minum siamang di habitat aslinya. Menurut Rosyid
(2007), cara minum siamang di alam yaitu dengan mendulang air dengan telapak
tangan dari lubang batang pohon, kemudian dialirkan ke dalam mulut sambil
menjilati tangannya.
40
Gambar 12. Aktivitas minum siamang betina di PPS Tegal Alur
Pada siamang betina (Noni), persentase aktivitas minum merupakan
aktivitas kedua setelah makan, kemudian diikuti dengan aktivitas urinasi dan
defekasi. Noni biasanya melakukan aktivitas minum setelah aktivitas makan
selesai. Aktivitas minum berhubungan dengan aktivitas bergerak siamang selama
di kandang, dimana semakin tinggi siamang melakukan berbagai macam gerakan
maka akan lebih tinggi siamang untuk minum. Selain itu aktivitas minum
berhubungan juga dengan aktivitas makan. Pakan berupa buah dan sayur segar
mengandung air yang tinggi sehingga semakin tinggi aktivitas makan, maka
aktivitas minumnya akan rendah. Hal ini dapat dilihat dari individu-individu
siamang jantan yang banyak menghabiskan pakan berupa buah segar untuk
memenuhi kebutuhan airnya dalam sehari. Buah-buahan yang diketahui
mengandung banyak air, yaitu semangka, timun dan sawi. Dalam penelitian
Yohanna et al. (2014), primata lain seperti owa jawa terlihat jarang
mengkonsumsi air, karena diduga kebutuhan air telah terpenuhi dari buah-buahan
yang dikonsumsi. Kappeler (1981) menambahkan, kebutuhan air pada primata
dapat dipenuhi dari buah-buahan dan bahan makanan lainnya. Tiga sumber utama
air pada tubuh hewan berasal dari air minum, air pada bahan makanan dan air
metabolik yang didapat sebagai hasil oksidasi makanan (McDonald et al., 2010).
41
(A) (B)
Gambar 13. Aktivitas urinasi (A) dan defakasi (B) siamang jantan di PPS Tegal
Alur
Rata-rata persentase aktivitas urinasi siamang di PPS Tegal Alur sebesar
1,48% (Gambar 10). Aktivitas urinasi siamang biasanya diawali dengan
melakukan aktivitas bergerak pada kandang, kemudian diam di suatu tempat
sambil berpegangan pada sel atap kandang dan kedua kaki berpegangan pada
bagian bawah kandang seperti posisi jongkok (Gambar 13). Urinasi pada siamang
betina (Noni) dilakukan di bagian bawah kandang, sedangkan pada individu-
individu siamang jantan dilakukan di bagian atas sel kandang.
Aktivitas urinasi dipengaruhi oleh asupan makanan dan faktor lingkungan.
Selama pengamatan aktivitas urinasi siamang betina (Noni) lebih tinggi dibanding
individu-individu siamang jantan. Hal ini disebabkan oleh asupan makanan
berupa air yang lebih banyak dikonsumsi. Oleh karena itu, aktivitas minum yang
tinggi diikuti dengan banyaknya siamang melakukan urinasi. Faktor lingkungan
yang mempengaruhi aktivitas urinasi adalah suhu lingkungan dan aktivitas
pembersihan kandang. Keeper membersihkan kandang siamang pada pagi hari
membuat kandang menjadi basah dan terkadang terkena bagian tubuh siamang.
Rata-rata kelembapan udara sekitar kandang yang tinggi membuat suhu
lingkungan kandang menjadi lebih rendah, sehingga aktivitas urinasi menjadi
cukup tinggi. Oleh karena itu, salah satu penyebab tinggi rendahnya aktivitas
urinasi adalah suhu lingkungan yang berubah-ubah. Menurut Anggraeni (2006),
suhu lingkungan yang tinggi memungkinkan terjadinya proses penguapan
(evaporasi) air dalam tubuh sehingga tubuh membutuhkan cairan. Guna
42
memenuhi kebutuhan air dan mencegah terjadinya dehidrasi, maka air yang
terdapat di dalam tubuh dipertahankan.
(A) (B) (C)
Gambar 14. Tekstur feses padat-cair (A), padat (B) dan cair tidak terbentuk (C)
(Medical Youth Research Club, 2018) pada siamang di PPS Tegal
Alur
Aktivitas defekasi dan urinasi merupakan bagian dari aktivitas membuang
kotoran dari tubuh. Aktivitas defekasi memiliki tanda-tanda yang hampir mirip
dengan aktivitas urinasi, namun perbedaannya hanya pada zat yang dikeluarkan,
yaitu pada urinasi berbentuk cairan berupa urin, sedangkan defekasi berbentuk
padatan berupa feses. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa rata-rata persentase
aktivitas defekasi menempati urutan terakhir pada perilaku yang berhubungan
langsung dengan pola makan, yaitu sebesar 0,99%. Tinggi rendahnya aktivitas
defekasi dipengaruhi oleh metabolisme tubuhnya, konsumsi pakan dan pada
tingkat pencernaannya. Diantara semua siamang di PPS Tegal Alur, siamang
betina (Noni) terlihat lebih banyak melakukan aktivitas defekasi. Padahal
individu-individu siamang lainnya lebih banyak mengonsumsi pakan yang
diberikan. Hal ini diduga karena organ pencernaan pada Noni tidak dapat
mengolah secara sempurna bahan pakan yang telah dikonsumsi. Menurut NRC
(2003), ciri khas sistem pencernaan kelompok frugivora yaitu memiliki lambung
yang relatif sederhana dan dinding yang licin, saluran usus kecil yang pendek dan
memiliki sekum.
4.4.2. Perilaku yang tidak berhubungan langsung dengan pola makan
Perilaku yang tidak berhubungan langsung dengan pola makan terdiri dari
aktivitas grooming, lokomosi dan istirahat. Rata-rata persentase aktivitas tertinggi
pada siamang di PPS Tegal Alur, yaitu aktivitas istirahat sebesar 43,21%, diikuti
43
aktivitas bergerak sebesar 21,42%, kemudian aktivitas grooming sebesar 17,14%
(Gambar 10).
Aktivitas grooming yang dilakukan yaitu auto-grooming (membersihkan
tubuh sendiri) yang ditandai dengan pencarian kotoran atau ektoparasit di sekujur
tubuhnya. Aktivitas ini dimulai dengan mencari kotoran tersebut di sela-sela
rambut, menjilat kemudian mengunyahnya (Rahman, 2011). Aktivitas grooming
selama pengamatan dengan frekuensi tertinggi terjadi pukul 10.00 WIB - 13.00
WIB, pada waktu tersebut siamang telah mendapatkan asupan makanan yang
cukup sehingga dilakukan aktivitas istirahat yang biasanya dibarengi dengan
aktivitas grooming. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahayu (2007), bahwa di
habitat aslinya primata banyak melakukan aktivitas beristirahat dan grooming
dibawah pohon pada saat suhu udara tinggi (siang) sampai menunggu suhu udara
turun.
Persentase aktivitas grooming siamang di PPS Tegal Alur memiliki nilai
lebih tinggi jika dibandingkan dengan aktivitas lainnya seperti makan dan minum,
yaitu 17,14%. Tingginya aktivitas tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor,
diantaranya yaitu pakan yang hanya tersedia pada waktu-waktu tertentu dan
sedikitnya pengayaan kandang di ruang lingkup siamang, sehingga siamang
banyak melakukan aktivitas istirahat yang diselingi dengan aktivitas grooming.
Berbeda seperti apa yang siamang lakukan di alam, mereka memiliki lebih banyak
pilihan untuk beraktivitas, seperti mencari makan di dahan-dahan pohon, bersosial
dan bermain dengan individu lainnya. Penelitian Sari & Harianto (2015)
menyebutkan bahwa siamang di Repong Damar Pahmungan melakukan aktivitas
grooming sesekali saat siamang-siamang dalam kelompok tersebut berinteraksi
(allo-grooming). Perilaku primata lain seperti monyet ekor panjang di Cagar
Budaya Ciung Winara menunjukkan aktivitas makan yang lebih tinggi
dibandingkan dengan aktivitas grooming (Rahayu, 2007).
Secara umum siamang di PPS Tegal Alur melakukan aktivitas grooming
dengan membersihkan diri dari kotoran dan parasit dengan cara meraba,
menggaruk, menjilat dan menggigit. Menggaruk merupakan tingkah laku yang
sering dilakukan pada auto-grooming. Beberapa kali juga terlihat siamang
menggigit parasit yang ditemukan di sekujur tubuhnya. Siamang memulai
44
aktivitas grooming-nya dengan mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat,
lalu meraba bagian tubuh yang kotor atau gatal, kemudian dilanjutkan dengan
menggaruk bagian tubuh tersebut. Posisi tubuh siamang saat grooming bermacam-
macam, bisa dalam posisi terbaring, miring, duduk, menggantung, hingga
telentang.
Aktivitas bergerak siamang di habitat aslinya terdiri dari jalan, berlari,
memanjat, menuruni pohon dan brakiasi (Rahman, 2011). Pergerakan siamang
yang mendominasi yaitu brakiasi. Hampir 80% dari pergerakannya bergantung di
dahan pohon (Gron, 2008). Selama di kandang aktivitas bergerak siamang lebih
terbatas, yaitu hanya terdiri dari jalan, memanjat, menuruni sel kandang dan
brakiasi. Siamang di PPS Tegal Alur memiliki rata-rata persentase aktivitas
bergerak sebesar 21,42%. Sebagian besar siamang selama pengamatan memiliki
tipe gerakan yang beragam, seperti berjalan, brakiasi, hingga memanjat dan
menuruni sel kandang. Tak jarang terlihat siamang yang hanya melakukan
pergerakan brakiasi dan jalan jongkok saja, seperti pada siamang betina (Noni)
dan satu individu siamang jantan (Mency). Aktivitas brakiasi siamang dilakukan
pada jeruji besi bagian atas kandang. Rendahnya aktivitas bergerak disebabkan
oleh ukuran kandang yang terbatas sehingga memperkecil ruang bergerak
siamang. Pengayaan kandang yang minim juga mampu mengurangi aktivitas
gerak siamang selama di kandang.
(A) (B)
Gambar 15. Aktivitas bergerak dan bersuara siamang jantan (A) dan betina (B) di
PPS Tegal Alur
Faktor lain yang mempengaruhi aktivitas bergerak adalah lingkungan
sekitar. Terkadang siamang bertingkah lebih aktif apabila merasa bahaya
mendekat, seperti kedatangan keeper atau peneliti. Hal ini ditandai dengan
45
munculnya gerakan brakiasi dan memanjat ke atas sel saat kandang siamang
dibersihkan. Siamang juga banyak melakukan gerakan ketika mengeluarkan suara.
Kantung suara (gullar sac) yang dimiliki siamang mampu mengeluarkan suara
yang keras untuk menandakan daerah teritorialnya. Selama pengamatan, siamang
betina (Noni) biasanya memulai mengeluarkan suaranya, kemudian diikuti oleh
individu-individu siamang jantan dan primata lainnya seperti owa jawa. Siamang
dengan primata lainnya aktif bersuara pada pagi menjelang siang hari pukul 09.00
WIB – 10.00 WIB. Tidak terlihat adanya aktivitas suara yang dilakukan di pagi
hari karena tidak banyak hal yang dapat dilakukan siamang pada pagi hari.
Menurut Sari dan Harianto (2015), salah satu aktivitas pertama yang dilakukan
siamang di pagi hari adalah bersuara.
Aktivitas istirahat siamang di PPS Tegal Alur merupakan aktivitas yang
paling dominan dibandingkan dengan aktivitas lainnya. Di habitat alaminya,
siamang melakukan aktivitas istirahat dengan cara merebahkan badannya pada
pohon (Gron, 2008). Menurut Ganesa dan Aunurohim (2012), aktivitas istirahat
ditandai dengan keadaan dimana siamang tidak melakukan aktivitas apapun,
hanya sekedar berbaring, tiduran dan duduk. Aktivitas istirahat memiliki rata-rata
persentase tertinggi dibanding dengan aktivitas harian lainnya, yaitu sebesar
43,21% (Gambar 10). Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian yang dilakukan
di penangkaran seperti Sharafina (2017), menyatakan bahwa aktivitas tertinggi
yang dilakukan siamang adalah aktivitas beristirahat (56%), kemudian Mahardika
(2008) juga menyebutkan aktivitas istirahat merupakan aktivitas dominan dari
owa jawa dibanding dengan aktivitas lainnya.
(A) (B) (C)
Gambar 16. Aktivitas istirahat siamang betina saat duduk (A), rebahan (B) dan
jantan saat duduk (C) di PPS Tegal Alur
46
Tinggi rendahnya aktivitas bergerak dan beristirahat dipengaruhi oleh
suhu. Demi menjaga agar kondisi tubuhnya tetap stabil, pada suhu yang tinggi
(siang hari), siamang banyak melakukan aktivitas istirahat sambil melakukan
grooming. Suhu udara yang tinggi dapat menguras energi dan cairan tubuh
siamang, oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut siamang mengurangi
aktivitas pergerakannya. Posisi tubuh siamang saat istirahat bervariasi, mulai dari
duduk sampai merebahkan tubuhnya di alas kandang (Gambar 16). Saat suhu
udara sangat panas, biasanya individu-individu siamang jantan duduk di dalam
kotak kayu tempat tidurnya atau jendela kandang, sambil sesekali memejamkan
matanya.
Faktor lain yang membuat aktivitas istirahat mendominasi perilaku harian
dikarenakan kecilnya ruang lingkup tempat tinggal siamang. Siamang yang berada
di kandang tentunya memiliki aktivitas yang lebih terbatas dibandingkan dengan
di habitat aslinya yang bergerak bebas ke tempat yang diinginkan, seperti
lokomosi, mencari makan dan bersosial. Pada habitat aslinya banyak pakan yang
tersedia sehingga siamang bebas bergerak untuk memilih pakan apa saja yang
diinginkan, namun di PPS Tegal Alur siamang hanya diberikan pakan yang
terbatas dan pada waktu-waktu tertentu saja.
47
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Siamang di PPS Tegal Alur diberikan pakan sebanyak tiga kali sehari,
yaitu pada pukul 07.00 WIB, 13.00 WIB dan 15.00 WIB. Pihak PPS Tegal Alur
memberikan pakan berupa sembilan jenis buah, dua jenis sayur dan satu jenis
dedaunan. Pakan diberikan dalam bentuk yang sudah terpotong dan utuh
kemudian diletakkan di tempat pakan permanen siamang. Vitamin diberikan
sebanyak seminggu sekali. Siamang di PPS Tegal Alur sudah memenuhi jumlah
konsumsi pakan sesuai dengan bobot tubuhnya. Status gizi berdasarkan
antropometri menunjukkan bobot tubuh siamang belum sesuai dengan habitat
alaminya. Pengamatan morfologi memperlihatkan kondisi gigi dan mata siamang
sehat, sedangkan beberapa siamang memiliki kondisi rambut yang rontok dan
mengalami depigmentasi. Konsumsi gizi berupa protein dan lemak pada seluruh
siamang belum memenuhi standar kebutuhan.
5.2. Saran
Dalam menunjang kualitas kandang sebaiknya pengelola PPS perlu
melakukan pengayaan kandang, seperti penambahan furnitur yang memuat bagian
ruang tengah dan atas kandang agar siamang mampu mengekspresikan sifat-sifat
dan perilaku alaminya. Pencatatan informasi satwa meliputi profil satwa dan
kesehatan fisik secara periodik membantu pengelola untuk menemukan tanda-
tanda awal adanya perilaku abnormal yang memperburuk kesehatan fisik,
sehingga tindakan yang diperlukan dapat diambil. Dalam pemberian pakan perlu
adanya penyediaan serangga dan penambahan jenis dedaunan sebagai salah satu
kebutuhan pakan alami siamang. Selain itu, sebaiknya pengelola tetap
menyediakan wadah minum kepada tiap siamang dan buah-buahan segar yang
diberikan pada siang hari untuk mengurangi rasa panas dan menghilangkan haus.
48
DAFTAR PUSTAKA
Akbar, H. (2011). Perawatan dan rehabilitasi satwa tangkapan di Pusat Penyelamatan
Satwa Cikananga, Sukabumi dan Gadog, Bogor. (Skripsi). Institut Pertanian Bogor,
Bogor.
Alikodra. (1990). Pengelolaan satwa liar jilid 1. Bogor, Indonesia: Institut Pertanian
Bogor.
Altmann, J. (1974). Observational study of behavior: sampling methods. Allee
Laboratory of Animal Behavior, University of Chicago, Chicago, Illinois, U.S.A.,
49, 227–265. https://doi.org/10.1080/14794802.2011.585831.
Anderson, M. R. (2014). Reaching new heights: the effect of an environmentally
enhanced outdoor enclosure on gibbons in a zoo setting. Journal of Applied Animal
Welfare Science, 17(3), 216–227.
Andriansyah, O. (2005). Studi adaptasi perilaku siamang (Hylobates syndactylus) pada
habitat yang mengalami aktivitas perladangan di Taman Hutan Raya Wan Abdul
Rachman. (Skripsi). Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
Bandar Lampung. Tidak dipublikasikan.
Atmanto, A. D., Dewi, B. S., & Nurcahyani, N. (2014). Peran siamang (Hylobates
syndactylus) sebagai pemencar biji di Resort Way Kanan Taman Nasional Way
Kambas Lampung. Sylva Lestari, 2(1), 49–58.
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Lampung. (2007). Daftar satwa
dilindungi. Lampung, Indonesia: BKSDA Lampung.
Bennett, B., Abee, C., & Henrickson, R. (1995). Nonhuman primates in biomedical
research - 1st edition (p. 428) (2020, July 30). Retrieved from
https://www.elsevier.com/books/nonhuman-primates-in-biomedical-research/benn
ett/978-0-12-088661-6.
BMKG. (2020). Prakiraan Cuaca (2020, May 20). Retrieved from https://www.bmkg.
go.id/cuaca/pra kiraan-cuaca-indonesia.bmkg.
Burek, J.D., P. Duprat, R. Owen, C.P. Peter, and M.J. Van Zwieten. (1988).
Spontaneous renal disease in laboratory animals. Int. Rev. Exp. Path, 30, 231-319.
Chivers, D. (1974). The siamang in Malaya. Evolution, 30, 196. https://doi.org/
10.1111/j.1558-5646.1976.tb00901.x.
Christyanti, M. (2014). Kompetisi dan tumpang-tindih relung antara siamang
(Symphalangus syndactylus) dan mamalia arboreal lainnya di Taman Nasional
Bukit Barisan Selatan. (Skripsi). Dept Biologi, Universitas Indonesia.
49
Church, D. C. (1976). Digestive physiology and nutrition of ruminant. vol. 1. digestive
physiology. 2nd edition. Oregon, Portland: Metropolitan Point. https://doi.org/10.
3168/jds.s0022-0302(70)86388-3.
CITES. (2020). Convention on international trade in endangered species of wild fauna
and floran (2020, February 2). Retrieved from http://cites.org/eng /app/appendices
.php.
Dunbar, R., & Cowlishaw, G. (2000). Primate conservation biology. Chicago, Illnois:
University of Chicago Press.
Elly, F. H., Manese, M. A. V., & Polakitan, D. (2013). Pemberdayaan kelompok tani
ternak sapi melalui pengembangan hijauan di Sulawesi Utara. Journal of Tropical
Forage Science, 53(9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/C BO9781107415324
.004.
Fleagle, J. G. (1988). Locomotor behavior and skeletal morphology of two sympatric
pitheciine monkeys, Pithecia pithecia and Chiropotes satanas. American Journal
of Primatology, 16(3), 227–249. https://doi.org/10.10 02/ajp.1350160305.
Fountain. (2011). Primate factsheets: siamang (symphalangus syndactylus) taxonomy,
morphology, & ecology (2020, February 22). Retrieved from http://pin.primate.
wisc.edu/factsheets/entry/siamang.
Ganesa, A., & Aunurohim. (2012). Perilaku harian harimau sumatera (Panthera tigris
sumatrae) dalam konservasi ex-situ Kebun Binatang Surabaya. Jurnal Sains Dan
Seni Its, 1(1), 48–53.
Geissmann, T. (1995). Hylobatidaes systematic and species identification. International
Zoo News, 42(8), 467–501.
Gron. K.J. (2008). Primate factsheets: siamang (Symphalangus syndactylus)
taxonomy, morphology, and ecology (2020, June 20). Retrieved from
http://pin.primate.wisc.edu/factsheets/.
Harianto. (1998). Habitat dan tingkah laku siamang (Hylobates syndactylus) di
taman nasional way kambas. (Tesis). Fakultas Pascasarjana IPB, Bogor. Tidak
dipublikasikan.
Kappeler. (1981). The Javan silvery gibbon (Hylobates moloch): ecology and
behaviour. (2020, June 23). Retrieved from http://www.markus kappeler.ch
/gib/fragib.html.
Karyawati, A. (2012). Tinjauan umum tingkah laku makan pada hewan primata. Jurnal
Penelitian Sains, 15(1), 44-47.
KSDAE, D. (2015). Keputusan direktur jendral konservasi sumber daya alam dan
50
ekosistem. Nomor: SK. 180/IVKKH/2015 tentang penetapan dua puluh lima satwa
terancam punah prioritas untuk ditingkatkan populasinya sebesar 10% Pada Tahun
2015-2019. Ditjen KSDAE, Jakarta.
Kurniawaty, N. D. (2009). Pendugaan kebutuhan nutrien dan kecernaan pakan pada
lutung kelabu (Trachypithecus cristatus, Raffles 1812) di Pusat Penyelamatan
Satwa Gadog Ciawi, Bogor. (Skripsi). Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Kuswanda, W., & Garsetiasih, R. (2016). Daya dukung dan pertumbuhan populasi
siamang (Hylobates syndactylus Raffles, 1821) di Cagar Alam Dolok Sipirok,
Sumatera Utara. Buletin Plasma Nutfah, 22(1), 67–8. https://doi.org/10.21082
/blpn.v22n1.2016.p67-80.
Kuswanda, W., Rozza Tri Kwatrina, Barus, S., Karlina, E., Rinaldi, D., & Pratiara.
(2019). Siamang : dari riset menuju konservasi. Bogor, Indonesia: Percetakan IPB.
Mahardika. (2008). Pemilihan pakan dan aktivitas makan owa jawa (Hylobates moloch)
pada siang hari di Penangkaran Pusat Penyelamatan Satwa, Gadog - Ciawi.
(Skripsi). Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Mann, G.V. (1968). Blood changes in experimental primates fed purified diets:
pyridoxine and riboflavin deficiency. Vit. Horm, 26, 465-485.
Maple, T. L., & Perkins, L. A. (1995). Enclosure furnishings and structural
environmental enrichment. In D. G. Kleiman, M. E. Allen, K. V. Thompson, & S.
Lumpkin (Eds.), Wild mammals in captivity. Chicago, Illinois: University of
Chicago Press.
Masy’ud, & Ginoga. (2016). Penangkaran satwa liar. Bogor, Indonesia: IPB Press.
McDonald, & Edwards, R. A. (1923). Animal nutrition. Nature, 111(2793), 651.
https://doi.org/10.1038/111651a0.
Medical Youth Research Club. (2018). Did you know?? feses anda aneh? berikut
penjelasannya (2020, September 22). Retrieved from https://med.unhas.ac.id/myrc
2018/12/21/did-you-know-feses-anda-aneh-berikut-penjelasannya/.
Meijaard. E, Rijksen HD, Kartikasari SN. (2001). Diambang kepunahan! kondisi
orangutan liar di awal abad ke-21. Jakarta, Indonesia: The Gibbon Foundation
Indonesia.
Mootnick, A. (1997). Management of gibbons hylobates spp at the international center
for gibbon studies, California: with a special note on pileated gibbons
hylobates.pileatus. International Zoo Yearbook, 35(1), 271–279. https://doi.org/10
.1111/j.1748-1090.1997.tb01220.x.
Mubarok. (2012). Distribusi dan kepadatan simpatrik ungko (Hylobates agilis) dan
siamang (Symphalangus syndactylus) di Kawasan Hutan Batang Toru, Sumater
51
Utara. (Skripsi). Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Myers, N., Mittermeier, R., Mittermeier, C. et al. (2000). Biodiversity hotspots
for conservation priorities. Nature, 403, 853–858.
NIDirect. (2014a). Welfare of primates: physical health (2020, June 20). Retrieved from
http://www. nidirect.gov.uk/welfare-of-primates-physical-health.
NIDirect. (2014b). Welfare of primates: the need for a suitable diet | nidirect Gov.Uk
(2020, June 20). Retrieved from https://www.nidirect.gov.uk/ articles/welfare-
primates-need-suitable-diet.
Nijman, V., & Geissman. (2006). In-situ and ex-situ status of the Javan Gibbon and the
ole of zoos in conservation of the species. Contributions to Zoology, 75(3–4), 161–
168. https://doi.org/10.1163/18759866-0750304005.
Nijman, V., & Geissman. (2008). IUCN red list of threatened species. choice reviews
online, 49, 49-6872-49–6872. https://doi.org/10.5860/choice.49-6872
National Research Council. (1998). The psychological well-being of nonhuman
primates. in the psychological well-being of nonhuman primates. Washington, DC:
The National Academies Press.
National Research Council. (2003). National research council. nutrient requirements of
nonhuman primates, 2nd revised edition. Washington, DC: The National
Academies Press
Palombit, RA. 1997. Inter- and intraspesific variation in the diets of sympatric siamang
(Hylobaes syndactylus) and lar gibbon (Hylobates lar). Folia Primatol, 68, 321-
337.
Perkins, L. A. (1992). Variables that influence the activity of captive orangutans. Zoo
Biology, 11(3), 177–186. https://doi.org/10.1002/zoo.1430110306.
PERSAGI. (2008). Tebel komposisi pangan Indonesia. Jakarta, Indonesia: Elex Media
Komputindo.
Prayudhi, R. T. (2015). Penegakan hukum, rehabilitasi dan pelepasliaran satwa
dilindungi hasil sitaan negara ujung tombak upaya penstabilan ekosistem kawasan
konservasi. Researchgate, 1–18.
Protection, E. A. (2000). Policy on exhibiting primates in New South Wales. New South
Wales: NSW Agriculture.
Rahayu, R. (2007). Aktivitas makan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis)
kelompok pancalikan periode juni-agustus di cagar budaya ciung wanara Ciamis,
Jawa Barat. (Skripsi). Institut Pertanian Bogor, Bogor.
52
Rahman, D. A. (2011). Studi aktivitas dan pakan owa jawa (Hylobates moloch) di Pusat
Studi Satwa Primata IPB dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango: penyiapan
pelepasliaran. (Tesis). Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Rasmada, S. (2008). Analisis kebutuhan nutrien dan kecernaan pakan pada owa jawa
(Hylobates moloch) di Pusat Penyelamatan Satwa Gadog-Ciawi Bogor. (Skripsi).
Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Rinaldi, D. (1992). Penggunaan metode triangle dan concentration count dalam
penelitian sebaran dan populasi gibbon (Hylobatidae). Media Konservasi, 4(1), 9–
21.
Rini Anggraeni (IPB). (2006). Perilaku yang berhubungan dengan pola makan walabi
kecil (Dorcopsulus vanheurni) betina di penangkaran pada siang hari (Institut
Pertanian Bogor) (2020, July, 30). Retrieved from http://helios-
eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/13107.
Rino. (2009). Pusat penyelamatan satwa (2020, January 2). Retrieved from
http://bksdadkijakarta.com/kawasan/pusat-penyelamatan-satwa/.
Ross, S. R., Calcutt, S., Schapiro, S. J., & Hau, J. (2011). Space use selectivity by
chimpanzees and gorillas in an indoor-outdoor enclosure. American Journal of
Primatology, 73(2), 197–208. https://doi.org/10.1002/ajp.20891.
Rosyid, A. (2007). Perilaku makan siamang dewasa (Hylobates syndacylus Raffles,
1821) yang hidup di hutan terganggu dan tidak terganggu. Agroland, 14, 237–240.
Santosa, Y., Nopiansyah, F., Mustari, A. H., & Rahman, D. A. (2010). Penggunaan
parameter morfometrik untuk pendugaan umur siamang sumatera (Symphalagus
syndactylus Raffles, 1821). Jurnal Pendidikan Hutan dan Konservasi Alam, 25–33.
Sari, E., & Sugeng, H. (2015). Studi kelompok siamang (Hylobates syndactylus) di
Repong Damar Pahmungna Pesisir Barat. Jurnal Sylva Lestari, 3(3), (85-94).
Sharafina, D. (2017). Manajemen pakan dan perilaku harian siamang (symphalangus
syndactylus) di Taman Satwa Taru Jurug, Surakarta. (Skripsi). Institut Pertanian
Bogor, Bogor.
Sian, W. (2002). An evaluation of five zoos in Indonesia. Bangor, Wales: SEI
Consultancy Ltd.
Sibarani, C. L. (2012). Manajemen pakan orangutan Sumatera (Pongo abelii Lesson,
1827) di Pusat Reintroduksi Orangutan Sumatera (pros) provinsi Jambi. (Skripsi).
Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Sultan, K., Mansjoer, S. S., & Bismark, M. (2009). Populasi dan distribusi ungko
(Hylobates agilis) di Taman Nasional Batang Gadis, Sumatera Utara. Jurnal
Primatologi Indonesia, 6(1), 25–31.
53
Supriatna, J., & Ramadhan, R. (2016). Pariwisata primata Indonesia. Jakarta,
Indonesia: Yayasan Pustaka Onor Indonesia.
Thamaria, N. (2017). Penilaian status gizi. Indonesia: Kementrian Kesehatan Republik
Indonesia.
Than, K. (2006). Why eyes are so alluring. Retrieved June 20, 2020, from https://www.
livescience.com/4299-eyes-alluring.html.
Tillman, A., Lebdosukojo, S., R, S., & H, H. (1991). Data Ilmu Makanan Untuk
Indonesia. Utah: International Feedstuffs Institute.
Tiyawati, A., Harianto, S. P., & Widodo, Y. (2016). Kajian perilaku dan analisis
kandungan gizi pakan drop in siamang (Hylobates syndactylus) di taman agro
satwa dan wisata bumi kedaton. Jurnal Sylva Lestari, 4(1), 107 - 114.
WCS-IP. (2000). Siamang lestari. Jakarta, Indonesia: Wildlife Conservation Society
Indonesia Program.
Yanuar. (2009). The gibbons: new perspectives on small ape socioecology and
population biology. Choice Reviews Online, 47, 47-1422-47–1422. https://doi.org/
10.5860/choice.47-1422.
YGI. (2006). Penyelamatan satwa (2020, January 2). Retrieved from
http://www.gibbon-donesia.org/?option=com_content&view=article&id=8&I
temid=20.
Yohanna, Masy’ud, B., & Mariastuti, A. (2014). Tingkat kesejahteraan dan status
kesiapan owa jawa di pusat penyelamatan dan rehabilitasi satwa untuk
dilepasliarkan. Media Konservasi, 19(3), 183–197.
Yuliana R. (2011). Analisis habitat siamang (Hylobathes syndactilus) di repong damar
pekon pahmungan kecamatan pesisir tengah lampung barat. (Skripsi). Universitas
Lampung, Lampung.
54
LAMPIRAN
Lampiran 1. Pakan siamang di PPS Tegal Alur
Salak Sawi Wortel Pisang Kepok
(Salacca zalacca) (Brassica chinensis) (Daucus corota) (Musa cuminata balbisiana)
Daun Pepaya Jambu Biji Jeruk Semangka
(Carica papaya) (Psidium guajava) (Citrus sinensis) (Citrullus lanatus)
Kacang Panjang Timun Pepaya Pisang Lampung
(Vigna unguiculata) (Cucumis sativus) (Carica papaya) (Musa paradisiaca)
55
Lampiran 2. Perhitungan rata-rata faktor fisik kandang siamang betina
Hari Ke-
Suhu Udara oC Kelembaban Udara (RH %) Kebisingan (Db) Intensitas Cahaya (Lux)
Waktu (WIB) Jam Jam Jam
7 13 16 7 13 16 7 13 16 7 13 16
1 31,2 31,5 28,9 60 62 61 50 38 48,3 909 2170 259
2 30,5 31,8 30 74 65 68 47 45,5 44,3 710 1155 615
3 31,6 30,1 31 72 78 61 49,7 45,8 46,7 758 909 484
4 31,1 317 30 57 66 68 42,9 47,1 47 1224 1349 520
5 33,1 33,,4 31 55 53 59 48,3 45,4 44,3 1093 710 390
6 28,8 30,6 31,4 73 73 70 48,5 46,9 50 140 615 707
7 31,2 30,3 30,7 69 74 70 51,3 45,6 44,6 608 259 370
8 30,6 33 29 60 61 61 50 41 48,3 909 2170 259
9 30 32 29,8 74 59 69 48 48 49,1 788 1349 702
10 31,4 30,3 30 72 61 65 53 44 47,1 980 890 520
11 30,2 31,2 29 57 65 70 44,5 47,9 51,2 1320 1272 489
12 32,4 32,9 30,3 58 53 62 46,9 44,1 45 930 756 401
13 29 30,5 31,1 71 63 71 50 48,3 49 210 758 698
14 32 31 30 71 73 77 42.9 47,1 45,4 710 320 298
SUM 433,1 4403 422,2 923 906 932 673 634,7 660,3 11289 14682 6712
AVG 30,93571 31,45 30,15714 65,92857 64,71429 66,57143 48,07143 45,33571 47,16429 806,3571 1048,714 479,4286
STDEV 1.20295 1.07971 0.81591 7.47780 7.57961 5.16965 3.00677 2.87392 2.23696 333.65 583.654 158.624
Lampiran 3. Perhitungan rata-rata faktor fisik kandang siamang jantan
Hari Ke-
Suhu Udara oC Kelembaban Udara (RH %) Kebisingan (Db) Intensitas Cahaya (Lux)
Waktu (WIB) Jam Jam Jam
7 13 16 7 13 16 7 13 16 7 13 16
1 32,7 31,7 30,2 68 60 70 49,8 37,8 44,1 9087 4458 1456
2 31 31,5 29 71 65 66 45 43,4 37,8 6009 5270 3249
3 30,8 29,8 29,8 73 78 67 525 40,7 49,5 11487 8955 9087
4 29,8 31,4 30.2 66 66 68 48,9 50,2 52,2 10872 5355 5752
5 32,6 32,7 31,1 61 54 60 52,8 45,1 45,7 16901 6009 1266
6 29 30,3 31,2 71 76 71 44,6 49,6 44,1 2601 10995 5752
7 33,9 30 30,4 57 74 70 49,2 48,8 49,2 10767 2875 1328
8 32,7 32,6 31 66 60 75 50,2 38 43,2 10872 4376 1534
9 30,8 32 30 76 58 69 45 43,4 40 7502 5752 2875
10 31,2 33,4 28,7 69 69 65 44 42,7 46,4 10995 8478 11334
11 28,7 31.4 30 63 66 62 49,2 51,5 50,4 9087 4458 4376
12 33 33 31.6 59 52 61 55 49,5 45,1 15387 5270 1328
13 28.2 31 31 74 57 72 44,6 50 40,7 3249 11766 7502
14 32 31 29,8 59 73 74 49,2 45,1 47 9087 3278 1266
SUM 436,4 441,8 424 933 908 950 680 635,8 635,4 133903 87295 58105
AVG 31,17143 31,55714 30,28571 66,64286 64,85714 67,85714 48,57143 45,41429 45,38571 9564,5 6235,357 4150,357
STDEV 1.754742 1.104337 0.835609 6.096747 8.346875 4.65514 3.486772 4.620166 4.145963 3964.1 2751.294 3299.235
56
Lampiran 4. Jumlah pakan yang diberikan selama 14 hari
Hari ke- Noni Sapri Pixy Gigih Mency Patrick Jumlah Rata-rata Standar deviasi
1 520 666 662 304 496 500 3148 524,6667 133.4026
2 554 473 594 400 589 585 3195 532,5 79.10689
3 685 769 473 359 580 576 3442 573,6667 146.1584
4 774 795 655 510 501 497 3732 622 139.2351
5 767 770 482 346 394 404 3163 527,1667 191.965
6 822 748 526 426 351 341 3214 535,6667 205.5185
7 676 824 689 500 768 773 4230 705 114.7833
8 508 582 566 664 761 646 3727 621,1667 88.75678
9 524 433 471 377 515 569 2889 481,5 69.23511
10 673 673 517 543 511 514 3431 571,8333 79.18691
11 740 776 515 337 357 392 3117 519,5 195.1417
12 710 670 485 395 395 366 3021 503,5 150.4377
13 757 691 719 536 702 790 4195 699,1667 87.9623
14 618 744 636 713 856 767 4334 722,3333 88.04241
Lampiran 5. Jumlah pakan sisa
Hari ke- Noni Sapri Pixy Gigih Mency Patrick Jumlah Rata-rata Standar deviasi
1 25 27 18 17 9 11 107 17,83333 7.22265
2 42 24 22 21 21 19 149 24,83333 8.565434
3 40 21 13 10 15 18 117 19,5 10.74709
4 34 26 17 30 24 22 153 25,5 5.991661
5 24 6 21 5 14 10 80 13,33333 7.840068
6 43 25 14 5 4 6 97 16,16667 15.3547
7 40 39 16 15 15 14 139 23,16667 12.67149
8 34 10 8 11 11 9 83 13,83333 9.948199
9 55 13 13 10 10 15 116 19,33333 17.58029
10 92 42 18 16 26 25 219 36,5 28.68972
11 67 29 12 5 9 12 134 22,33333 23.37235
12 31 23 13 5 8 3 83 13,83333 11.03479
13 89 46 13 13 12 21 194 32,33333 30.61808
14 73 26 13 16 21 16 165 27,5 22.75742
Lampiran 6. Jumlah pakan yang dikonsumsi
Hari ke- Noni Sapri Pixy Gigih Mency Patrick Jumlah Rata-rata Standar Deviasi
1 639 495 644 287 487 495 3047 507,8333 130,5962
2 449 512 572 379 568 560 3040 506,6667 78,13749
3 748 645 460 349 565 555 3322 553,6667 139,2116
4 769 740 638 480 477 474 3578 596,3333 137,7892
5 764 743 461 341 380 390 3079 513,1667 190,2666
6 723 779 512 421 347 350 3132 522 188,1276
7 785 636 673 485 753 759 4091 681,8333 111,8793
8 572 474 558 653 750 637 3644 607,3333 94,3544
9 420 469 458 367 505 554 2773 462,1667 65,06433
10 631 581 499 527 485 489 3212 535,3333 58,83423
11 747 673 503 332 348 380 2983 497,1667 176,9897
12 647 679 472 390 387 363 2938 489,6667 139,5932
13 645 668 706 523 690 769 4001 6668333 82,06684
14 718 545 623 697 835 751 4169 694,8333 100,9483
57
Lampiran 7. Kandungan Gizi Pakan Siamang di PPS Tegal Alur
Pakan Zat gizi dalam 100 gram pakan
Energi (Kal) Protein (g) Lemak (g) Karbohidrat (g) Air (g)
Daun Pepaya 87 8 2 11,9 75,4
Jambu Biji 49 0,9 0,3 12,2 86
Jeruk 45 0,9 0,2 11,2 87,2
Kacang Panjang 44 2,7 0,3 7,8 88,5
Pepaya 46 0,5 0 12,2 86,7
Pisang Kepok 109 0,8 0,5 26,3 71,9
Pisang Lampung 99 1,3 0,2 25,6 72,1
Salak 77 0,4 0 20,9 78
Sawi 22 2,3 0,4 4 92,2
Semangka 28 0,5 0,2 21,6 92,1
Timun 12 0,7 0,1 2,7 96,1
Wortel 42 1,2 0,3 9,3 88,2
Sumber : PERSAGI (2008)