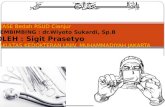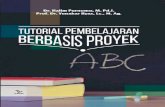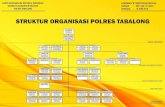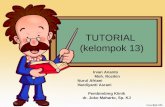Tutorial Dr. Wiyoto
-
Upload
lutfi-malefo -
Category
Documents
-
view
7 -
download
4
description
Transcript of Tutorial Dr. Wiyoto

Patofisiologi
Masuknya kuman Salmonell thypi (S. typhi) dan Salmonella parathypii (S. parathypi) ke
dalam tubuh manusia melalui makanan yang terkontaminasi kuman. Sebagian kuman
dimusnahkan oleh asam lambung, sebagian lolos masuk ke dalam usus dan selanjutnya
berkembang biak. Bila respon imunitas humoral mukosa (IgA) usus kurang baik maka kuman
akan menembus sel-sel epitel (terutama sel M) dan selanjutnya lamina propria. Di dalam lamina
propria kuman berkembang biak dan difagosit oleh sel-sel fagosit terutama oleh makrofag.
Kuman dapat hidup dan berkembang biak di dalam makrofag dan selanjutnya dibawa ke plaque
peyeri ileum distal dan kemudian ke kelenjar getah bening mesenterika. Selanjutnya melalui
duktus torasikus, kuman yang terdapat dalam makrofag ini masuk dalam sirkulasi darah
(mengakibatkan bakterimia I yang asimtomatis) dan menyebar ke seluruh organ
retikuloendotelial tubuh terutama hati dan limpa. Di organ-organ ini, kuman meninggalkan sel-
sel fagosit dan kemudian berkembang biak di luar sel atau ruang sinusoid dan selanjutnya masuk
ke dalam sirkulasi darah lagi, mengakibatkan bakterimmia yang kedua kalinya dengan disertai
tanda-tanda dan gejala penyakit infeksi sitemik.
Di dalam hati kuman masuk ke dalam kandung empedu, berkembang biak, dan bersama
cairan empedu di ekskresika secara intermiten ke dalam lumen usus. Sebagian kuman
dikeluarkan melalui feses dan sebagian masuk lagi ke dalam sirkulasi setelah menembus usus.
Proses yang terulang kembali, berhubung makrofag telah teraktifasi dan hiperaktif maka saat
fagositosis kuman Salmonella terjadi pelepasan beberapa mediator inflamasi yang selanjutnya
akan menimbulkan gejala reaksi inflamasi sistemik seperti demam, malaise, mialgia, sakit
kepala, sakit perut, instabilitas vaskular, gangguan mental, dan koagulasi.
Di dalam plaque paeyeri makrofag hiperaktif menimbulkan reaksi hiperplasia jaringan
(S. typhi intramakrofag menginduksi reaksi hipersensitifitas tipe lambat, hyperplasia jaringan,
dan nekrosis organ). Perdarahan saluran cerna dapat terjadi akibat erosi pembuluh darah disekitar
plaque peyeri yang sedang mengalami nekrosis dan hyperplasia akibat akumulasi sel-sel
mononuklear di dinding usus. Proses patologis jaringan limfoid ini dapat berkembang biak
hingga ke lapisan otot, serosa usus, dan dapat mengakibatkan perforasi.
Setelah terjadinya perforasi, maka debris, pus, sisa jaringan nekrotik, dan udara akan
keluar menuju cavum peritoneum sehingga menyebabkan kenaikan tekanan intra abdomen.
Penaikan tekanan intra abdomen akan mendorong diafragma menuju ke atas dan mendorong

paru-paru, sehingga volume kapasitan inspirasi paru yang masuk akan berkurang, lalu tubuh
akan menyeimbangkannya dengan pernafasan cepat (takipneu).
Endotoksin dapat menempel di reseptor sel endotel kapiler dengan akibat timbulnya
komplikasi seperti gangguan neuropsikiatrik, kardiovaskular, pernafasan, dangangguan organ
lainnya.
Gambaran Klinis
Penegakkan diagnosis sedini mungkin sangat bermanfaat agar bisa diberikan terapi yang
tepat dan meminimalkan komplikasi. Pengetahuan gambaran penyakit ini sangat penting untuk
membantu mendeteksi secara dini. Walaupun pada kasus tertentu dibutuhkan pemeriksaan
tambahan untuk membantu menegakkan diagnosis. Masa tunas demam tifoid berlangsung
anatara 10-14 hari. Gejala-gejala klinis yang timbul sangat bervariasi dari ringan sampai dengan
berat, dari asimptomatis hingga gambaran yang khas, disertai komplikasi hingga kematian.
Pada minggu pertama, gejala klinis penyakit ini ditemukan keluhan dan gejala serupa
dengan penyakit infeksi akut pada umumnya, yaitu demam, nyeri kepala, pusing, nyeri otot,
anoreksia, mual, muntah, obstipasi atau diare, perasaan tidak enak di perut, batuk, dan epistaksis.
Pada pemeriksaan fisik hanya didapatkan suhu badan meningkat. Sifat demam adalah meningkat
perlahan-lahan dan terutama pada sore hingga malam hari. Pada minggu kedua gejala-gejala
menjadi lebih luas, berupa demam, bradikardi relatif (bradikardi relatif adalah peningkatan suhu
1° C tidak diikuti dengan peningkatan denyut nadi 8x per menit), lidah yang berselaput (kotor di
tengah, tepi dan ujung merah serta tremor), hepatomegali, splenomegali, meteorismus, gangguan
mental berupa somnolen, stupor, delirium, atau psikosis.
Pemeriksaan Laboratorium
Pemeriksaan Darah Rutin
Walaupun pada pemeriksaan darah perifer lengkap sering ditemukan leukopenia, dapat
pula terjadi kadar leukosit normal atau lekositosis. Leukositosis dapat terjadi walaupun tanpa
disertai infeksi sekunder. Selain itu pula dapat ditemukan anemia ringan dan trombositopenia.
Pada pemeriksaan hitung jenis leukosit dapat terjadi aneusinofilia maupun limfopenia. Laju
endap darah dalam demam tifoid dapat meningkat.
SGOT dan SGOT sering kali meningkat, tetapi akan kembali menjadi normal ketika
sembuh. Kenaikan SGOT dan SGPT tidak memerlukan penanganan khusus.

Pemeriksaan lain yang rutin dilakukan adalah uji Widal dan kultur organisme. Sampai
sekarang, kultur masih menjadi standar baku dalam penegakkan diagnostic. Selain uji widal,
terdapat beberapa metode pemeriksaan serologi lain yang dapat dilakukan dengan cepat dan
mudah serta memiliki sensitifitas dan spesifisitas lebih baik, antara lain uji TUBEX, Typhidot,
dan dipstick.
Uji Widal
Uji widal dilakukan untuk deteksi antibodi terhadap kuman S. thypi. Pada uji widal
terjadi suatu reaksi aglutinasi antara antigen kuman S. typhi dengan antibodi yang disebut
aglutinin. Antigen yang digunakan pada uji widal adalah suspense Salmonella yang sudah
dimatikan dan diolah di laboratorium. Maksud uji Widal adalah untuk menentukan adanya
agglutinin pada serum penderita tersangka demam tifoid yaitu: (a) agglutinin O (dari tubuh
kuman); (b) agglutinin H (flagella kuman); (c) agglutinin Vi (simpai kuman).
Dari ketiga agglutinin tersebut, hanya agglutinin O dan H yang digunakan untuk
diagnosis demam tifoid. Semakin tinggi titernya semakin besar kemungkinan terinfeksi kuman
ini.
Pembentukan agglutinin mulai terbentuk pada akhir minggu pertama demam, kemudian
meningkat secara cepat dan mencapai puncak pada minggu ke-4 dan tetap tinggi selama
beberapa minggu. Pada fase akut mula-mula timbul agglutinin O, kemudian diikuti dengan
agglutinin H. Pada orang yang telah sembuh, agglutinin O masih tetap dijumpai setelah 4-6
bulan, sedangkan agglutinin H menetap lebih lama, antara 9-12 bulan. Oleh karena itu uji Widal
bukan untuk menentukan kesembuhan penyakit.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi uji Widal yaitu: (1) pengobatan dini dengan
antibiotik; (2) gangguan pembentukan antibodi dan pemberikan kortikosteroid; (3) waktu
pengambilan darah; (4) daerah endemic atau non-endemik; (5) riwayat vaksinasi; (6) reaksi
anamnestik, yaitu peningkatan titer agglutinin pada infeksi bukan demam tifoid akibat infeksi
demam tifoid masa lalu atau vaksinasi; (7) faktor teknik pemeriksaan antar laboratorium, akibat
aglutinasi silang, dan strain Salmonella yang digunakan untuk suspensi antigen.
Saat ini belum ada kesamaan pendapat mengenai titer agglutinin yang bermakna
diagnosis untuk demam tifoid. Batas titer yang sering dipakai hanya kesepakatan saja, hanya
berlaku setempat, dan batas ini bahkan dapat berbeda di berbagai laboratorium setempat.

Penatalaksanaan
Sebagai dokter umum, tindakan pertama kali yang harus dilakukan adalah menentukan
apakah kasus ini termasuk emergensi atau elektif. Setelah itu boleh dilakukan perujukan, namun
harus menstabilkan keadaan umum pasien.
Rehidrasi dengan cairan Ringer Laktat untuk resusitasi akibat muntah yang terjadi dapat
dilakukan pada kasus ini karena pada saat terjadi muntah, terjadi asidosis metabolik. Setelah
dilakukan resusitasi, jika terjadi peritonitis, maka dilakukan tindakan dekompressi dengan
pemasangan Nasogastric Tube (NGT) dan kateter untuk menurunkan tekanan intra abdomen.
Pemberian anti-emetik, boleh diberikan namun tidak boleh dengan obat anti-emetik yang
bersifat lokalis yang dapat menurunkan peristaltik usus karena dapat memperberat peritonitis.
Pemberian analgetik yang dapat menurunkan nyeri secara perifer, seperti ketorolac, dapat
diberikan serta antibiotik yang sensitif terhadap bakteri anaerobik.