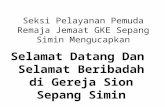Tradisi Pisowanan di daerah Banyumas sebagai Model Liturgi...
Transcript of Tradisi Pisowanan di daerah Banyumas sebagai Model Liturgi...
1
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
1.1. Agama dan Kebudayaan
Agama sebagai sebuah usaha manusia untuk membentuk kosmos keramat, di samping
berhubungan dengan hal yang bersifat gaib, supranatural dan yang tidak terjangkau oleh akal,
juga berkaitan dengan perkembangan suatu masyarakat.1 Sebagai sebuah sistem kepercayaan,
agama melegitimasikan pranata-pranata sosial masyarakat dengan meletakkannya ke dalam
suatu kerangka acuan yang bersifat kosmik dan keramat. Dengan demikian, sebagaimana
dinyatakan oleh Clifford Geertz, agama adalah :
sebuah sistem simbol-simbol yang berlaku untuk menetapkan suasana hati
(moods) dan motivasi-motivasi yang kuat, yang meresap dan tahan lama dalam
diri manusia, dengan merumuskan konsep-konsep mengenai suatu tatanan umum
eksistensi dan membungkus konsepsi ini dengan semacam pancaran (aura)
faktualitas, sehingga suasana hati (moods) dan motivasi-motivasi itu nampak khas
realistis.2
Agama sebagai sebuah sistem kebudayaan membungkus fenomena alam dan perilaku
masyarakat dengan tatanan relijius tertentu yang diyakini dan dihayati bersama dengan
pemaknaan di dalamnya. Konsepsi bermakna tersebut membentuk pola yang diteruskan
secara historis dan diwujudkan dalam simbol-simbol, yang dengannya manusia
berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan mereka tentang kehidupan
dan sikap-sikap terhadap kehidupan tersebut.3
1 H. Djamari, Agama dalam Perspektif Sosiologis, (Bandung: Alfabeta, 1992), h.77. 2 Clifford Geertz, Kebudayaan dan Agama, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 5. 3 Ibid, h. 4.
@UKDW
2
Dalam kaitannya dengan kebudayaan lama Indonesia, Jakob Sumardjo menjelaskan konsepsi
Ketuhanan masyarakat Indonesia yang terkait dengan kondisi alam sekitarnya. Konsep
“Tuhan” dalam kebudayaan Indonesia lama dilihat sebagai totalitas, yang terwujud dalam
harmoni oposisi. Mengikuti pandangan Rudolf Otto, Sumardjo menegaskan bahwa Tuhan
yang dihayati masyarakat Indonesia lama bersifat memikat (fascinosum) sekaligus
menakutkan (tremendum).4 Maka, tidak mengherankan pada apa terungkap dari pandangan
masyarakat lereng Gunung Merapi yang ditulis Sindhunata, “Tuhan itu dahsyat, tapi indah,
Dia mematikan tetapi juga menghidupkan, Dia jauh tapi dekat, Dia menuntut banyak tetapi
juga memberi dengan murah hati, Dia kaya raya tetapi juga sangat sederhana”5.
1.2. Agama dan Bencana
Berdasarkan Undang-undang no. 24 tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana, yang
dimaksud dengan bencana adalah :
peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan
dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau
faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis. 6
Bencana, entah itu bencana alam maupun non-alam, pada dasarnya menjadi sebuah persoalan
ketika ada kena mengenanya dengan manusia. Hal ini nampak jelas pada bencana sosial yang
tidak jarang terjadi mengikuti sebuah bencana alam/non-alam. Maka tepat ketika Prof.
Bernard T. Adeney mengemukakan bahwa bencana alam dan bencana manusia tidak
4 Jakob Sumardjo, Arkeologi Budaya Indonesia, (Yogyakarta: Qalam, 2002), h. 3-10, band. Rudolf Otto, The Idea of
the Holy (London: Oxford University Press, 1958), h.12-40 5 Sindhunata, Mata Air Bulan, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 175. Dikutip E. Gerrit Singgih, dalam Allah dan
Penderitaan di Dalam Refleksi Rakyat Indonesia, dalam Zakaria J. Ngelow, dkk (ed.), Teologi Bencana, (Makassar:
Oase Intim, 2006), h. 254. 6 Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang no. 24 tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana, h. 2.
@UKDW
3
bermakna dalam dirinya sendiri Kita sebagai manusia harus membangun maknanya sendiri.
Makna bencana terkait erat dengan bagaimana kita menanggapinya.7
Pemaknaan yang dilakukan manusia dalam situasi bencana seringkali tidak lepas dari
pemaknaan secara teologis. Paling tidak ada tiga sudut pandang tanggapan terhadap situasi
bencana : secara agamis, mitologis dan ilmiah.8 Sejalan dengan hal ini, Furedi
mengungkapkan tiga jejak pandangan mengenai penyebab bencana, yakni sebagai “karena
Allah”, “karena alam”, dan “karena manusia”.9
1.3. Gunung Merapi
Gunung Merapi sudah sangat lama dikenal sebagai gunung yang indah. Keindahan itu sangat
memberi berkah bagi masyarakat di sekitar Merapi. Kawasan yang terletak pada ketinggian
600-2986 meter di atas permukaan laut dan secara administratif berada di kawasan Propinsi
D.I. Yogyakarta (sekitar 1550 ha) serta Jawa Tengah (sekitar 6447 ha). Potensi alam dan
keindahan Merapi semakin didukung oleh interaksi yang harmonis antara penduduk dengan
alam di kawasan tersebut. Keindahan dan kelimpahan berkah yang didapat dari Gunung
Merapi ini di sisi lain menyimpan potensi ancaman. Dengan siklus erupsi yang pendek, yakni
antara 2 – 5 tahun, masyarakat di sekitarnya memiliki persepsi tersendiri terhadap keberadaan
dan aktivitas vulkanik gunung tersebut.
Masyarakat Dusun Kinahrejo, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten
Sleman DIY sudah begitu akrab dengan Gunung Merapi. Masyarakat disana sangat
mempercayakan kondisi mereka berkaitan dengan aktivitas Gunung Merapi, kepada juru
kuncinya yaitu Mbah Marijan. Kapan mereka harus mengungsi dan kapan mereka harus
bertahan di dusunnya semua tergantung kepada ‘instruksi’ dari Mbah Marijan. Konsepsi
masyarakat terhadap keberadaan Gunung Merapi menguatkan kepercayaan mereka bahwa
mereka tidak akan diganggu oleh letusan Gunung Merapi.
7 Bernard T. Adeney, “Pendahuluan”, dalam Teologi Bencana, (ibid), h. 37. 8 Andreas A.Yewangoe, “Membangun Teologi Bencana – Pergumulan Teodice dan Teologi Penderitaan Allah”,
dalam dalam Ngelow, Zakaria J., dkk (ed.), Teologi Bencana, h. 222-224. 9 Furedi, F., 2007. “The Changing Meaning of Disaster” Area Bulletin, vol. 39, April 2007, h. 483–485
@UKDW
4
Sikap masyarakat yang enggan meninggalkan tempatnya bermukim untuk mengungsi dari
bencana Merapi, dapat dipahami sebagai sebuah sikap hidup yang mengandung nilai-nilai
rasa kecintaan, keterikatan, kepemilikan, kesetiaan, dalam berhubungan dengan alam semesta
Merapi sebagai tempat hidup. Masyarakat lereng Merapi pada umumnya, memandang Merapi
secara positif, lebih melihat sebagai anugerah ketimbang sebagai sumber musibah.
Ungkapan-ungkapan lokal yang dipakai untuk menyebut Merapi dengan segala
aktivitasnyapun senantiasa bernada positif. Misalnya ungkapan ”Mbah buyut lagi dandan-
dandan” (Eyang buyut sedang berbenah) atau “Simbah lagi duwe gawe” (Eyang sedang
punya hajat”, untuk mengungkapkan peristiwa erupsi Merapi menjadi salah satu contoh
ungkapan yang bernada positif atas aktivitas gunung ini. Ada ikatan yang sulit dijelaskan
antara penduduk kawasan Merapi dengan Gunung Merapi. Minsarwati menjelaskan bahwa
manusia yang berdiam di kawasan Merapi berkedudukan sebagai mikrokosmos atau jagat
cilik, sedang Gunung Merapi sebagai makrokosmos atau jagat gedhe. Keduanya memiliki
hubungan yang erat, sebagai satu kesatuan, yang bersifat timbal-balik.10
Konsepsi masyarakat terhadap keberadaan Gunung Merapi menguatkan kepercayaan mereka
bahwa mereka tidak akan diganggu oleh letusan gunung merapi. Mereka, yang dibiasakan
memanggil gunung tersebut dengan sebutan Mbah Merapi akan mengatakan kalau Mbah
Merapi sedang dandan-dandan (berbenah diri), duwe gawe (punya hajat) atau resik-resik
(bersih-bersih) ketika Gunung Merapi mengeluarkan lahar atau erupsi. Mereka juga percaya
bahwa lahar Mbah Merapi tidak akan sampai ke dusun mereka karena percaya bahwa dusun
mereka merupakan pelataran rumah Mbah Merapi sehingga Mbah Merapi tidak akan
membuang sampah di pelatarannya sendiri. Mereka juga percaya bahwa di dusun mereka
bersemayam bibinya Mbah Merapi sehingga tidak mungkin Gunung Merapi memutahkan
laharnya ke dusun mereka.11
10 Wisnu Minsarwati, Mitos Merapi dan Kearifan Ekologi: Menguak Bahasa Mitos Dalam Kehidupan Masyarakat
Jawa Pegunungan, (Yogyakarta, 2002), h. 79. 11 Penelitian Kearifan Lokal di Daerah Bencana, oleh Tim Peneliti Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kebudayaan
Badan Pengembangan Sumberdaya Budpar – Kemenbudpar, Juli – Agustus 2010, di mana penulis terlibat di
dalamnya.
@UKDW
5
1.4. Upaya Kontekstualisasi Teologi Bencana Gereja Kristen Jawa (GKJ)
Gereja Kristen Jawa (GKJ), tempat penulis melayani, dewasa ini sedang mendalami dan
mempergumulkan jalan baru dalam berteologi : Teologi Lokal, dimana Teologi Bencana ada
di dalamnya. Sebagai sebuah gereja etnis (Jawa) yang hidup di tengah konteks bergereja dan
bermasyarakat yang dinamis, GKJ menyadari perlunya sebuah upaya kontekstalisasi dalam
berteologi. Hal ini tercermin dalam Artikel Sidang Sinode XXIV12 :
Setelah membahas:
1. Laporan Deputat Pengembangan Kepemimpinan tentang penerimaan utusan dari
Protestant Church in the Netherlands (PCN) dalam diri Ibu Josien Folbert dan Pdt.
Jaspert Slob sebagai tenaga ahli dalam program teologi lokal, teologi bencana, dan
teologi lintas agama bersama Yayasan Persemaian Cinta Kemanusiaan (Percik)
Salatiga
2. Laporan Deputat Keesaan tentang pengembangan teologi lokal
3. Masukan Ibu Josien Folbert tentang pemahaman teologi lokal
Sidang memutuskan:
1. Menerima laporan tersebut dan menugasi Bapelsin untuk menindaklanjuti program
pengembangan teologi lokal, teologi bencana, dan teologi lintas agama bersama
Yayasan Percik.
2. Mendorong Gereja-gereja untuk mengembangkan teologi lokal, teologi bencana, dan
teologi lintas agama.
12 Artikel 33, Akta Sidang Sinode GKJ XXIV, di Wirobrajan, Yogyakarta
@UKDW
6
yang dilanjutkan dalam Sidang Sinode GKJ XXV, tahun 200913 :
Menanggapi rekomendasi kelompok Kerja Berteologi Lokal tentang program teologi
bencana;
Sidang mempertimbangkan:
1. Indonesia termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
2. Bencana menimbulkan kompleksitas persoalan yang tinggi, yang perlu dihadapi dan
dijawab secara teologis.
Sidang memutuskan:
Menugasi Kelompok Kerja Teologi Lokal untuk melanjutkan program teologi bencana.
Pergumulan teologis GKJ tersebut dipicu dengan situasi kebencanaan di tanah air, khususnya
mulai dengan adanya peristiwa Gempa Bumi di Yogyakarta, pada 27 Mei 2006, yang turut
meluluhlantakkan 46 gereja GKJ di wilayah Klaten, Bantul, Sleman, Kulonprogo.14 Bukan
hanya bangunan gereja dan rumah jemaat yang porak poranda, namun peristiwa tersebut
cukup mengguncang bangunan teologis jemaat GKJ. Ditambah dengan adanya Erupsi Merapi
tahun 2010, yang sekalipun tidak berdampak banyak dan langsung kepada jemaat/gereja-
gereja GKJ, namun mengingat wilayah persebaran gereja cukup banyak di sekitar lereng
Gunung tersebut, maka Sinode GKJ memandang perlu untuk menggali Teologi Bencana
seperti apa yang dapat dihidupkan dan dikembangkan dalam konteks seperti itu.
Sebagai tindak lanjut keputusan Sidang Sinode tersebut, bekerjasama dengan Yayasan Percik
Salatiga, diadakan serangkaian seminar untuk menggali Teologi Lokal tersebut (I: 14-15 April
13 Artikel 17, Akta Sidang Sinode GKJ XXV, di Kaliurang, Yogyakarta 14 Laporan Pokja Pemulihan Korban Gempa Sinode GKJ (2007), h. 22
@UKDW
7
2008 ; II: 10-11 Juni 2008 ; III: 27-28 November 2008 ; IV: 12-13 November 2009)15. Dari
rangkaian seminar tersebut, semakin disadari ketegangan dalam upaya berteologi di GKJ,
antara teologi “resmi”, yang notabene sangat kental dengan teologi “Barat”, berhadapan
dengan teologi “lokal” yang masih banyak dihidupi oleh kaum awam GKJ namun seringkali
terpinggirkan.16 Namun demikian, rangkaian seminar itu belum sampai pada pembicaraan dan
pergumulan mengenai Teologi Bencana sebagaimana diamanatkan dalam Akta Persidangan
Sinode GKJ XXIV.
Baru pada tahun 2011 – sesudah Sidang Sinode GKJ XXV, Bidang Litbang Sinode GKJ
XXV bekerjasama dengan Yayasan Percik memfasilitasi Pokja Penanggulangan Bencana
Sinode GKJ menyelenggarakan Lokakarya Penanggulangan Bencana bertempat di Pondok
Remaja Salib Putih, Salatiga. Bidang Litbang dan Kespel bersama Pokja Penanggulangan
Bencana sempat membicarakan perihal teologi bencana. Beberapa pertanyaan pun muncul
dalam Lokakarya tersebut, terkait dengan program pengembangan teologi bencana,
diantaranya:
Siapa sesungguhnya yang berhak berteologi atas bencana?
Darimana starting point program teologi bencana dimulai? Penyintas17, yang
terkadang bahkan seringkali bukan anggota jemaat, relawan ataukah teolog/pendeta?
Kemudian, pendekatan seperti apakah yang dipakai?
Di balik pertanyaan-pertanyaan tersebut ada kebutuhan penting yang menjadi dasar program
teologi bencana ini. Jangan sampai program teologi bencana hanya didasari dari apa kata
orang tentang bencana. Dari seminar tersebut, dipandang penting untuk mendengarkan orang
yang mengalami bencana dan menjadi penyintas/korban. Dalam konteks hidup bergereja,
15 Sebagaimana disarikan dan dilaporkan dalam buku yang diterbitkan Pudjaprijatma, Sinode GKJ dan Yayasan
Percik, Pdt., dkk (Ed.) “Kata Pengantar”, dalam Pijar-pijar Berteologi Lokal : Berteologi Lokal dari Perspektif
Sejarah dan Budaya. (Salatiga, 2010), h. xxiii-xxvi 16 Pudjaprijatma, dkk (Ed.) “Kata Pengantar”, dalam Pijar-pijar Berteologi Lokal : Berteologi Lokal dari Perspektif
Sejarah dan Budaya. (Salatiga, 2010), h. xxvii. 17 Terminologi “korban” untuk sebuah peristiwa bencana telah diganti dengan terminologi “penyintas” yang menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti lebih positif, yakni terus bertahan hidup, mampu
mempertahankan keberadaannya, sehingga penyintas didefinisikan sebagai orang yang mampu bertahan hidup.
@UKDW
8
perlu dilihat bahwa GKJ punya pengalaman dengan kebencanaan. Ketika ada bencana, GKJ
ada, hadir, dan terlibat di situ. Entah itu sebagai korban, penyintas, relawan, hingga
keterlibatan para pendetanya di tengah-tengah situasi bencana. Dari pengalaman perjumpaan
dengan para penyintas, ada sinyal bahwa penyintas membutuhkan jawaban teologis atas
situasi yang menimpa. Bagi relawan juga membutuhkan refleksi teologis dari apa yang
dilakukan dalam karya kemanusiaan. Berteologi bencana lintas iman menjadi perhatian ketika
sinode GKJ melalui litbangnya, Lembaga Percik, forum SOBAT (persaudaraan lintas agama)
berkumpul di Kampoeng Percik, 19 April 2011, untuk merefleksikan pengalaman
kebencanaan. Paham berteologi bencana lintas iman didasari fakta bahwa bencana memang
tidak pandang bulu.18
Sebagai salah satu lokasi hidup jemaat GKJ, daerah sekeliling lereng Merapi
(Sleman/Yogyakarta, Muntilan, Magelang dan Klaten) menghadapi situasi kebencanaan yang
bisa datang setiap saat. Di tengah bangunan Teologi Bencana yang belum rapih tersusun,
dirasa akan bermanfaat sekiranya jemaat dapat belajar dari mereka yang benar-benar berada
pada titik episentrum erupsi Merapi, sekaligus pusat spiritual Jawa terkait hubungan antara
Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Gunung Merapi, dan yang secara turun-temurun
akrab dengan bencana akibat erupsi gunung berapi. Dengan melakukan studi ini diharapkan
akan lebih menemukan Kristus dalam situasi, ketimbang memusatkan perhatian pada usaha
membawa Kristus ke dalam situasi tersebut, sebagaimana langkah kontekstualisasi yang
diyakini oleh Schreiter.19 Maka dalam kerangka berteologi kontekstual atas bencana ini,
penulis akan mencoba menggali teologi-teologi lokal dari mereka yang notabene justru bukan
komunitas Kristen, sekalipun bukan berarti tidak mengalami perjumpaan dengan kekristenan,
terlebih dalam situasi-situasi kebencanaan.
18 Notulen pertemuan, disarikan oleh Pdt. Setiyadi. 19 Robert J. Schreiter, Rancang Bangun Teologi Lokal, (Jakarta, 2006), h. 64-65.
@UKDW
9
2. Rumusan masalah
Bagaimanapun, Gunung Merapi menjadi pusat refleksi masyarakat di lereng gunung
tersebut.20 Dengan peristiwa alamiah yang dilihat, dialami dan dimaknai, sebuah kelompok
masyarakat membangun teologianya, yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya –
bahkan seringkali berbeda dan tak terduga oleh para ahli/peneliti, untuk sebuah peristiwa
yang sama. Oleh karena itu, menjadi penting untuk dapat menggali persepsi masyarakat
lereng Gunung Merapi terhadap situasi alam sekitar mereka, dalam hal ini erupsi dari gunung
teraktif di dunia yang menjadi salah satu dari enam belas Gunung teraktif di dunia (Decades
of Vulcano)21 ini.
Sebelum erupsi besar tahun 2010, masyarakat Kinahrejo pada umumnya memandang positif
keberadaan Gunung Merapi dengan segala aktivitasnya. Mereka percaya bahwa dusun
mereka – Kinahrejo sebagai “Pelataran Merapi” tidak mungkin terkena dampak erupsi
gunung tersebut. Ungkapan yang sering muncul adalah “Kalau Simbah Merapi duwe gawe
(punya hajat), tidak mungkin membuang sampahnya ke pelataran depan rumahnya”.
Demikian pula pandangan dan kepercayaan terhadap Juru Kunci, Mbah Maridjan, sebagai
simbol penghubung mereka dengan makhluk Illahi penunggu gunung, sedemikian kuatnya.
Hal yang cukup signifikan berbeda terjadi, tatkala Gunung Merapi meletus hebat pada tahun
2010. Erupsi beruntun dari tanggal 26 Oktober 2010 dan berpuncak tanggal 5 November
2010 meluluh-lantakkan dusun-dusun di Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo, termasuk
Dusun Kinahrejo, tempat tinggal Mbah Maridjan – Juru Kunci Gunung Merapi, bahkan
menewaskannya. Peristiwa tersebut seakan menyentak kesadaran mereka bahwa dusun yang
mereka percayai sebagai “pelataran Merapi” itu ternyata bisa terkena dampak negatif erupsi,
bahkan hancur berantakan. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Surono,
menyatakan letusan Merapi 2010 merupakan bencana terburuk Merapi sejak 1870, karena
20 E. Gerrit Singgih, “Allah dan Penderitaan di Dalam Refleksi Rakyat Indonesia”, dalam Ngelow, Zakaria J., dkk
(ed.), Teologi Bencana, h. 253. 21 http://vulcan.wr.usgs.gov/Volcanoes/DecadeVolcanoes/ (Diakses tanggal 12 Mei 2011)
@UKDW
10
dalam letusan kali ini sebanyak 32 desa dengan jumlah penduduk lebih dari 70.000 jiwa
direkomendasikan harus mengungsi karena berada dalam zona berbahaya,22
Pertanyaannya kemudian adalah, seiring dengan letusan besar yang meluluhlantakkan desa
yang mereka percayai sebagai “pelataran Merapi” dan turut menewaskan juru kunci
terpercaya mereka, bagaimana pemahaman dan penghayatan warga Kinahrejo terhadap
Merapi dengan segala aktivitasnya pasca erupsi 2010 ini? Atau dengan kata lain, bagaimana
bangunan teologi atau sistem kepercayaan – terkait dengan Gunung Merapi dengan segala
aktivitasnya ini?
3. Tujuan Penelitian/Penulisan
Dengan penelitian dan penulisan tesis ini bertujuan sebagai berikut:
1. Menginventarisasi dan mendokumentasikan pengetahuan teologis masyarakat Dusun
Kinahrejo terhadap situasi bencana yang diakibatkan oleh aktivitas erupsi Gunung
Merapi, Yogyakarta, yang pada gilirannya bisa menjadi sebuah pembanding dan bisa
menjadi sebuah alternatif berteologi lokal kontekstual atas bencana bagi Gereja
Kristen Jawa.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi aksi bantuan maupun pendampingan yang bisa
dilakukan gereja ataupun kelompok masyarakat lain, dengan tetap memperhatikan
bangunan teologis yang dimiliki masyarakat yang menjadi korban bencana tersebut
Dengan menggali dan menemukan bangunan teologis masyarakat lokal lereng Merapi
pasca erupsi 2010 ini, apa yang bisa dilakukan oleh gereja/komunitas lain dengan
memperhatikan lingkaran pastoral/hermenutik berikut ini:
22 http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/10/11/05/144681-letusan-merapi-2010-terburuk-sejak-
1870 , (diakses tanggal 5 November 2010)
@UKDW
11
interpretasi
Analisis Planning / Action
Observasi
4. Landasan Teori
Indonesia memiliki keaneka-ragaman budaya dan setiap budaya memiliki cerita tradisional
(mitos) untuk menjaga lingkungan hidup mereka. Dekker J. Mouboi juga menyatakan dalam
tulisannya, bahwa cerita, di satu pihak menghubungkan manusia dengan masa lampaunya,
serentak dengan itu pula, di pihak lain, cerita mengungkapkan visi dan cita-cita masa depan
manusia.23 Manusia dalam arti tertentu dibentuk oleh dan melaui cerita, dan oleh karena itu
kelanjutan hidup suatu kelompok masyarakat ikut ditentukan oleh kemampuan kelompok
tertentu dalam menciptakan cerita mereka sendiri dan melanjutkannya kepada generasi
berikutnya.24
Untuk itu, Dekker dalam tulisannya menyarankan bahwa di samping cerita penciptaan di
dalam Alkitab, hendaknya gereja tidak mengabaikan berbagai cerita rakyat yang sangat kaya
kandungan pedagogisnya dalam rangka membangun suatu pandangan dunia yang utuh
dengan kesadaran dan tanggung jawab yang tulus terhadap lingkungan hidup.25
Maka, dalam upaya menggali cerita yang bisa menjadi titik pijak upaya berteologi lokal
dalam konteks bencana ini, penulis memakai kerangka teori kearifan lokal (local wisdom)
Paradigma ini penulis pakai karena sesuai dengan sistem kepercayaan Jawa yang oleh E.
23 Dekker J. Mouboi, “Ekologi dalam PAK”, dalam buku Andar Ismail, Ajarlah Mereka Melakukan (Jakarta, 2004),
h. 99. 24 ibid, h. 100 25 ibid
@UKDW
12
Gerrit Singgih disebut sebagai agama “kosmis”.26 Paradigma ini juga dipilih untuk
menghindari dominasi dan pemaksaan makna terhadap masyarakat Kinahrejo sendiri sebagai
pelaku budaya, sehingga didapatkan gambaran kearifan lokal sebagai sebuah upaya
masyarakat sendiri berteologi atas kesadaran dan realitas lingkungannya, Gunung Merapi.
Kearifan lokal (local wisdom) dipahami sebagai perangkat pengetahuan pada suatu komunitas
untuk menyelesaikan persoalan dan/atau kesulitan yang dihadapi, yang diperoleh dari
generasi-generasi sebelumnya secara lisan, melalui contoh tindakan dan yang memiliki
kekuatan seperti hukum ataupun tidak.27 Lebih lanjut Heddy menambahkan bahwa sebagai
sebuah perangkat pengetahuan inter-generasi, kearifan lokal mencakup baik “kearifan
tradisional” maupun “kearifan masa kini/kontemporer”.28 Istilah local wisdom (kearifan
lokal) muncul, terutama setelah para ilmuwan di Barat menyadari bahwa ilmu pengetahuan
yang mereka miliki ternyata telah gagal membawa masyarakat non-Barat ke taraf kehidupan
yang lebih baik. Pengetahuan dan teknologi Barat yang ditransfer pada masyarakat yang
dianggap tradisional gagal untuk menyelesaikan masalah lokal, bahkan terkadang
menimbulkan masalah baru yang lebih rumit dan sulit diatasi. Kesadaran akan kegagalan ilmu
pengetahuan dan teknologi Barat tersebut – menurut Heddy – telah mendorong mereka untuk
menengok pada dan mempelajari pengetahuan-pengetahuan lokal yang sudah ada selama
puluhan, bahkan ratusan tahun dalam suatu masyarakat, dan telah memungkinkan masyarakat
pemiliknya bertahan hidup hingga sekarang.29
Bagi komunitas/masyarakat sendiri, kearifan lokal yang terakumulasi dalam narasi-narasi
tertulis maupun lisan dapat menjadi sumber data empiris bagi pengetahuan terkait persoalan
spiritualitas (dan teologis) dari persektif lokal.30 Dengan demikian kearifan lokal dapat
diidentifikasikan sebagai sikap, pandangan dan kemampuan suatu komunitas di dalam
26 E. Gerrit Singgih, Berteologi dalam Konteks, Pemikiran-pemikiran mengenai Kontekstualisasi Teologi di
Indonesia (Yogyakarta, 2007), h. 115. 27 Heddy Shri Ahimsa-Putra, Etnosains, Etnotek dan Etnoart – Paradigma Fenomenologis untuk Revitalisasi
Kearifan Lokal (Makalah yang disampaikan dalam “Seminar Pemanfaatan Hasil Riset UGM dalam Mendukung
Peningkatan Daya Saing Indonesia”, Yogyakarta, 28 November 2006), h. 6. 28 Ibid, h. 7 29 Heddy Shri Ahimsa-Putra, Kearifan Lokal–Wujud, Cara Mengenali dan Revitalisasinya (Makalah disampaikan
dalam workshop “Kewenangan Daerah Kota Yogyakarta terhadap Nilai-nilai Kebangsaaan” diselenggarakan oleh
Pemerintah Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 20 September 2011), h. 1. 30 Wening Udasmoro dan Joachim Agus Tridianto, Spiritualitas Warga Merapi – Agency dan Survival Strategy
Dalam Merespon Bencana (Yogyakarta, 2012), h.7-8.
@UKDW
13
mengelola lingkungan (rohani maupun jasmani), yang memberikan daya tahan dan daya
tumbuh bagi komunitas tersebut sebagai perangkat pengetahuan yang mampu menghadapi
suatu lingkungan, dan membentuk pola perilaku sehari-hari, baik terhadap sesama manusia
maupun terhadap lingkungan tersebut.
Pendekatan melalui kearifan lokal masyarakat yang berlatar belakang kepercayaan kosmik ini
sejalan dengan paradigma kosmik-holistik31, yang berpandangan bahwa pusat dari seluruh
sistem alam semesta bukanlah manusia (seperti dalam pandangan anthroposentris), tetapi
pusat kehidupan ini ada pada semua ciptaan. Paradigma kosmik-holistik ini juga memberi
perhatian terhadap komunitas ekologis seluruhnya, baik yang hidup maupun yang mati.
Secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lain.
Dalam paradigma kosmik-holistik tersebut, Banawiratma menyatakan bahwa:
1. Kenyataan dunia ini dilihat sebagai yang menyatu dengan Yang Ilahi, dan didekati
secara utuh dalam kesatuan dengan Yang Ilahi.
2. Alam merupakan sacramentum (tanda) dari kehadiran Yang Ilahi, yang dialami
melalui bentuk ungkapan perempuan dan laki-laki. Unsur dan perspektif perempuan
masuk dalam pengalaman akan yang ilahi.
3. Komunitas, termasuk ciptaan non-human, merupakan titik tolak dan orientasi dalam
memandang kenyataan hidup.
4. Keseluruhan martabat manusia dimengerti dari tanggungjawab bersama untuk
menempatkan diri dalam dan ikut serta memelihara alam semesta.
5. Segala sesuatu merupakan bagian-bagian yang secara terus menerus bertali temali,
suatau proses yang ditandai oleh interdependensi dan ko-operasi timbal balik. Dengan
demikian, “keseluruhan” lebih besar dari jumlah bagian-bagian..
31 J.B. Banawiratma, 10 Agenda Pastoral Transformatif: menuju pemberdayaan kaum miskin dengan perspektif adil
gender, HAM, dan lingkungan hidup, (Yogyakarta, 2002), h. 27
@UKDW
14
6. Karena keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagian maka pengertian
manusia selalu parsial dan harus selalu terbuka untuk pengertian baru dan lebih penuh,
untuk itu digunakan daya imajinasi.
7. Semua bentuk kehidupan mempunyai potensi khusus (inate) untuk mengatur diri.
Perubahan dan penyembuhan diakibatkan oleh atau terjadi dari dalam, atau barangkali
oleh pelaku perubahan dari luar.
8. Metafor dasariah dari paradigma ini adalah : holon (keseluruhan).
9. Semua potensi terbuka dalam proses yang ditempatkan dan dipelihara dalam
keseluruhan.
10. Partisipasi dari dan rasa bagi keseluruhan merupakan keutamaan dasariah.
Maka, sejalan dengan itu, penghayatan masyarakat sekitar lereng Merapi menganggap alam
sebagai saudara, sebagai akumulasi budaya Jawa di masa lalu, menjadi semakin terlihat.32
Bahwa nilai sebuah benda di alam semesta ini tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan atau
kepentingan manusia. Segala sesuatu di alam semesta ini dihargai karena mempunyai nilai
pada dirinya sendiri. Manusia hanya salah satu bentuk kehidupan yang pada prinsipnya sama
kedudukannya dalam tatanan ekologis.
Demi kepentingan penelusuran Teologi Lokal dan Teologi Bencana sebagaimana
diamanatkan dalam dua persidangan Sinode GKJ terakhir di atas, penulis mencoba
mengambil pendekatan Robert J. Schreiter, dengan lebih “mendengarkan budaya”, ketimbang
menerjemahkan tradisi (dan dogma) gereja ke dalam situasi lokal. Untuk sebuah studi
budaya, Schreiter menandaskan tiga karakteristik yang mesti ada di dalamnya, yakni33 :
32 E. Gerrit Singgih, Mengantisipasi Masa Depan – Berteologi dalam Konteks di Awal Milenium III, (Jakarta, 2005),
h.72. 33 Robert J. Schreiter, Rancang Bangun Teologi Lokal, (Jakarta, 2006), h.70-75.
@UKDW
15
1. Holistik : bahwa sebuah pendekatan budaya tidak bisa hanya berpusat pada satu
bagian budaya dan mengabaikan bagian lainnya. Maka dengan itu pula, pendekatan
ini tidak bisa mengabaikan “budaya populer/budaya rakyat” (tradisi dan praktek-
praktek rakyat) sebagai suatu entitas yang seolah lebih rendah dari “budaya tinggi”
(Agama resmi, karya seni ataupun ungkapan sastra yang dipandang tinggi), karena
bagi Schreiter, agama/kepercayaan bukan hanya suatu “pandangan hidup”, melainkan
sebuah “cara hidup”.
2. Jati diri : bahwa suatu pendekatan terhadap budaya harus mampu berbicara pada
kekuatan-kekuatan yang membentuk jati diri dalam suatu budaya tersebut. Sebuah
teologi lokal harus bisa memperhatikan dua dimensi kembar formasi jati diri : batas
kelompok dan pandangan dunia, yang pada gilirannya akan membentuk suatu
identitas budaya.
3. Perubahan sosial : bahwa suatu pendekatan terhadap budaya harus memperhatikan
proses perubahan sosial sebagai suatu keniscayaan dinamika dunia.
Teori dan paradigma berteologi lokal Schreiter ini menjadi penting dalam kerangka upaya
pencarian Teologi Bencana yang kontekstual yang menjadi tujuan penulisan Tesis ini.
Dengan memakai pendekatan budaya ini, penulis berharap bisa menemukan gambaran teologi
bencana yang dari perspektif lokal, karena, sebagaimana diyakini Sedmak, bahwa melalui
ekspresi budaya lokal inilah, kita dapat menemukan Allah yang melanjutkan karya
penciptaan-Nya.34
Setelah menemukan teologi lokal dalam konteks bencana erupsi gunung Merapi, pada
gilirannya akan diperlukan sebuah kerangka aksi pastoral yang berangkat dari sudut pandang
mereka yang terdampak bencana. Upaya ini menjadi penting, manakala banyak aksi
pastoral/pembantuan di tengah bencana lebih banyak berangkat dari sudut pandang dan
kepentingan “orang luar”, yang pada gilirannya menjadi tidak tepat sasaran atau bahkan
merusak harmoni di tengah masyarakat terdampak. Maka dalam tulisan ini perlu
34 Band. Clemenns Sedmak, Doing Local Theology, A Guide for Artisans f a New Humanity (New York, 2002) h..
73-74.
@UKDW
16
diketengahkan “Teori Kompleksitas Mutualis” (Mutual Complexity Theory) sebagaimana
diyakini Dorothe Hilhosrt.35 Dengan paradigma ini, Hilhosrt hendak memperlihatkan bahwa
hubungan antara risiko dan kerentanan terhadap bencana berkaitan dengan interaksi antara
alam dan masyarakat. Disamping menyoroti struktur masyarakat – sebagaimana ada dalam
kaum strukturalis, paradigma Mutual Complexity Theory ini juga menyoroti hubungan
masyarakat dan alam/lingkungannya.
Mengikuti pandangan Stacey36, dalam teori ini, Hilhorst menyampaikan tiga jalinan kompleks
antara “kekacauan” (chaos), “struktur yang galau” (dissipative structure) dan “sistem
adaptasi” (adaptive system). Dalam kekacauan, perubahan terjadi karena elemen-elemen yang
berbeda dalam suatu sistem terbuka berinteraksi satu dengan yang lain sehingga
menimbulkan perubahan-perubahan dengan pola yang tidak terduga. Ketidakterdugaan
(unpredictability) ini terutama berdasar pada “ketidakmampuan manusia dalam mengukur
ketepatan yang tidak terbatas”.37 Kompleksitas bertambah ketika terjadi ketidakseimbangan
akibat struktur dan sistem yang galau – karena perubahan kondisi. Pada akhirnya risiko dan
kerentanan terhadap suatu ancaman bencana juga bergantung pada sistem adaptasi yang
kompleks. Sistem adaptasi ini tergantung pada pengalaman (personal maupun komunal) dan
interaksi antara sistem lokal dengan yang dari luar – yang bisa sekedar sebuah interaksi
informasi.38 Interaksi tersebut terkadang membuat sistem adaptasi yang tidak terprediksi pula.
Hilhorst percaya bahwa sistem adaptasi yang tak terprediksi (the unpredictability of adaptive
system) yang tertuang dari interaksi kreatif dari agen-agen penalaran yang beragam tersebut
menawarkan solusi yang lebih tepat untuk memahami kerentanan dan bencana dalam tataran
kenyataan yang beragam (multiple realities).39
Teori kompleksitas mutual ini penulis pandang relevan bagi kajian teologi bencana karena ia
membuka pintu masuk bagi suatu penjelasan bencana sebagai sebuah interaksi antara sub-
35 Dorothe Hilhosrt, “Complexity and Diversity: Unlocking Social Domains of Disaster Respons, dalam Mapping
Vulnerability : Disaster, Development dan People, ed. by Greg Bankoff (British: Earthscan, 2004), h. 52-56, Band.
Siti Syamsiatun dan Benny Baskara, “Merengkuh Merapi dengan Iman, Peran Organisasi Berbasis Agama dalam
Penanganan Pasca Erupsi Merapi 2010-2011” (Yogyakarta: UGM, 2012), h 21-26. 36 Ibid, band. Stacey Menzel Baker, Vulnerability and Resilience in Natural Disasters: A Marketing and Public
Policy Perspective, h. 115-117 37 Hilhosrt, ibid, h. 55 38 Ibid 39 Ibid, h. 56.
@UKDW
17
sistem alam dan masyarakat, juga relasi antara risiko dan kerentanan. Dengan paradigma ini,
bencana bisa dilihat sebagai akibat dari interaksi antara beberapa sub-sistem dalam
lingkungan geofisik dan klimatologi di satu sisi dan sub-sistem kemasyarakatan – seperti
pengetahuan ilmiah, sistem keyakinan dan sistem pengetahuan lokal di sisi lain.
Dengan paradigma ini, penulis berharap bisa menemukan keunikan pola hubungan
masyarakat Dusun Kinahrejo sebagai lokasi Upacara Labuhan dengan struktur Dusun
maupun struktur Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sendiri. Di samping itu, dengan
paradigma tersebut, penulis dapat menemukan pola hubungan masyarakat dengan lingkungan
mereka yang menjadi landasan pandangan teologis setempat.
5. Judul Tesis
Berteologi Kontekstual atas Bencana
(Penghayatan Teologis Masyarakat Kinahrejo Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010)
6. Metode Penelitian
Untuk dapat “mendengarkan budaya”, seperti yang digulirkan Schreiter, penulis akan
melakukan penelitian dengan menggunakan metode etnografi baru yang memusatkan
usahanya untuk menemukan bagaimana suatu kelompok masyarakat mengorganisasikan
budaya mereka dalam pikiran mereka dan kemudian menggunakan budaya tersebut dalam
kehidupan. Metode yang dipelopori J. P.Spradley tersebut, menggunakan Alur Penelitian
Maju Bertahap, yakni melakukan penelitian eksploratif untuk menjajagi, mengenali,
menemukan, dan menginventarisasi potensi data budaya yang didukung oleh kelompok
@UKDW
18
masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dengan tiga garis besar alur penelitian yang terdiri
dari : pertanyaan deskriptif, pertanyaan pembuktian dan pertanyaan kontras.40
Untuk melengkapi data dan memperkuat teori demi analisis dan eksplorasi tesis ini, dilakukan
studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai tulisan khususnya yang terkait.
7. Alat penelitian
1. Wawancara
Penentuan responden untuk keperluan wawancara dilakukan dengan menggunakan
metode snowball sampling, artinya memilih responden dan nara sumber yang akan
berfungsi sebagai representasi dari kelompok masyarakat yang dijadikan obyek
penelitian. Pemilihan selain dilakukan secara random juga dengan mempertimbangkan
saran dari tokoh-tokoh masyarakat yang bersangkutan.
2. Live-in dalam komunitas
Live-in dalam komunitas diperlukan untuk lebih memahami pola dan cara hidup yang
dihayati oleh subyek penelitian.
8. Kerangka Penulisan Tesis
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini memaparkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan
penelitian/penulisan, landasan teori, judul tesis, metode penelitian, alat penelitian dan
sistematika penulisan.
40 James P Spradley, Metode Etnografi, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h. 61-64
@UKDW
19
BAB II : ERUPSI GUNUNG MERAPI TAHUN 2010 DAN DAMPAKNYA
TERHADAP PENDUDUK KINAHREJO
Bab ini akan menguraikan deskripsi dari hasil upaya menggali dan menguraikan gambaran
umum mengenai bencana dan Gunung Merapi.
BAB III : PANDANGAN TEOLOGIS MASYARAKAT KINAHREJO TENTANG
GUNUNG MERAPI
Dalam bab ini diuraikan pandangan teologis masyarakat daerah penelitian mengenai/terhadap
Gunung Merapi. Secara khusus akan digali pandangan teologis masyarakat daerah penelitian
pasca erupsi 2010 dan cerita-cerita umum yang terkait, termasuk di dalamnya adalah
kepercayaan masyarakat yang terakumulasi dalam mitos-mitos seputar Gunung Merapi. Bab
ini menjadi sebuah langkah observasi dan analisis penulisan tesis.
BAB IV : BERTEOLOGI KONTEKSTUAL ATAS BENCANA
Dalam bab ini akan dirumuskan Teologi kontekstual atas bencana terkait dengan keberadaan
Gunung Merapi dan aktivitas erupsinya. Teologi yang coba diurai dan dibangun dalam tesis
ini diharapkan akan berguna bagi praksis berteologi jemaat GKJ khususnya yang berada di
seputar lereng Gunung Merapi ataupun masyarakat pada umumnya. Penulis akan melakukan
langkah interpretasi terhadap hasil observasi/penelitian dan analisis yang disajikan dalam bab
sebelumnya. Untuk itu, dalam bab ini akan disampaikan pula rekomendasi aksi pastoral yang
dapat dilakukan bagi korban erupsi Merapi.
BAB V : PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan, saran dan penutup.
@UKDW