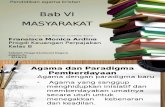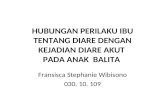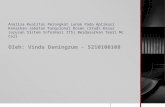Skripsi Fransisca Vinda Dinata 111.070.147
-
Upload
muchlis-irwanto -
Category
Documents
-
view
275 -
download
4
Transcript of Skripsi Fransisca Vinda Dinata 111.070.147
SKRIPSI
Oleh :
FRANSISCA VINDA DINATA
111.070.147
JURUSAN TEKNIK GEOLOGI
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL ”VETERAN”
YOGYAKARTA
2011
ANALISIS FASIES BATUBARA DAN KARAKTERISTIK
PETROFISIK, FORMASI BALIKPAPAN, LAPANGAN “X”,
CEKUNGAN KUTAI BERDASARKAN DATA LOG SUMUR DAN
INTI BATUAN
i
KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan
tugas akhir ini. Adapun judul tugas akhir ini adalah “Analisis Fasies Batubara dan
Karakteristik Petrofisik, Formasi Balikpapan, Lapangan “X”, Cekungan Kutai
Berdasarkan Data Log Sumur dan Inti Batuan “.
Penulis sangat berterima kasih pada dosen pembimbing yang telah memberikan
bimbingan serta petunjuk yang penulis perlukan dalam penulisan laporan tugas akhir
ini, keluarga penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis, serta teman-teman
jurusan Teknik Geologi UPN “Veteran” Yogyakarta yang telah memberikan semangat
serta masukan pada penulis.
Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada :
1. Ir. H. Sugeng Raharjo, MT., selaku Ketua Jurusan Teknik Geologi, Fakultas
Teknologi Mineral, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi di
VICO Indonesia.
2. Ir. Sugeng Widada, Ms.c. dan Ir. Ediyanto, M.T, selaku dosen pembimbing
skripsi di Jurusan Teknik Geologi.
3. Mr. Jose Corbellini selaku pembimbing teknis di VICO Indonesia, terimakasih
atas semua kesempatan, pengalaman, pengetahuan, bimbingan, masukan, bantuan
dan dukungan yang diberikan.
4. Mas Ratno Adi terimakasih atas pengentahuan, bimbingan, masukan dan bantuan
yang diberikan.
5. Mas Teguh Setiawan, Giscard, Asrim, Sutha, Taufik, dan Sigit atas diskusi dan
bantuan yang diberikan.
6. Bapak Amireno terimakasih atas masukan, bimbingan, dan bantuan yang sudah
diberikan.
7. Terimakasih banyak untuk Reservoir Modeling Team dan CBM Team VICO
Indonesia untuk penerimaannya yang baik.
ii
8. Saudara-saudaraku tercinta Antonius Firdian Zul Kurniawan, Veronica Dina
Angelia Sari, Florentina Fersa Andika, Emiliana Ayu Puspitasari, Mbak Lina,
Mas Oki, Mas Alex, Mbak Laras, Mas Lukas, Mbak Eta dan adik Cheris
terimakasih atas semua dukungan, semangat dan dorongan yang diberikan.
9. Hilda Nindiyah, Lenny Djulvalinda Miranti, Angga Widya Yogatama, Abang
Randy Dwi Anggara, Yolanda Titawael, Yenny Eva Oktri, Tiolina Hutagalung,
Novitalia Wijayanti, Jaquline Olivia Tanati, Fredy Prima Iriano, Yogi, Multihadi,
Aldis Ramadhan, dan yang lainnya yang tidak bisa disebut satu per satu yang
sudah memberikan semangat dan dorongan terimakasih banyak.
10. Pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan tugas akhir secara langsung
maupun tidak langsung yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
Penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan pada laporan penelitian ini,
maka dari itu penulis mengharapkan semua kritik dan masukan dari semua pihak yang
bersifat membangun demi hasil yang lebih baik sehingga di dalam pembuatan laporan
yang akan datang akan jauh lebih sempurna. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi
kita semua.
Yogyakarta , 5 Agustus 2011
Fransisca Vinda Dinata
iii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Skripsi ini dipersembahkan untuk :
Tuhan Yesus Kristus untuk semua kekuatan dan anugerah yang telah diberikan
selama ini. Terimakasih Tuhan karena Engkau aku dapat menyelesaikan skripsi
ini dengan lancar.
Ibuku yang sudah tidak lagi bersamaku lagi. Terimakasih Ibu karena engkau
telah melahirkanku, sehingga aku dapat menjadi seperti sekarang ini. Walaupun
engkau tidak bersamaku, aku hanya ingin kau tahu bahwa kau selalu ada di
dalam hatiku dan aku akan selalu merindukan dan menyayangimu.
Papi dan Mamiku tercinta terimakasih atas segala dukungan dan motivasi baik
materil maupun spritual yang telah diberikan kepadaku.
Saudara – saudaraku tercinta Veronica Dina Angelia Sari, Antonius Firdian
Zulkurniawan, Florentina Fersa Andika dan Emiliana Ayu Puspitasari atas segala
dukungan dan motivasi baik materil maupun spritual yang telah diberikan
kepadaku.
Seluruh saudara-saudaraku Pangea 2007 atas semua dukungan dan motivasinya.
Terimakasih semuanya.....
iv
Sari
Lapangan minyak “X” merupakan salah satu lapangan operasi Coalbed Methane milik VICO Indonesia yang terletak di Cekungan Kutai, Propinsi Kalimantan Timur. Analisis yang dilakukan ialah dengan melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif dengan mengkalibrasikan data log sumur dari 8 sumur dan data inti batuan. Fokus studi pada penelitian ini adalah mengidentifikasi model fasies pengendapan, mengidentifikasi karakteristik petrofisik dari batubara serta dari seam batubara CBM 2 yang termasuk dalam Formasi Balikpapan yang merupakan reservoar coalbed metahne dan mengidentifikasi distribusi parameter petrofisik pada seam tersebut.
Berdasarkan analisis elektrofasies tipe endapan berdasarkan model pengendapan menurut Horne, 1978 Seam CBM 2 yaitu endapan channel, swamp, interdistributary bay dan creavasse splay yang berasosiasi dengan lingkungan pengendapan Transitional lower Delta Plain dan berdasarkan analisis elektrofasies tipe fasies menurut model Allen, 1998, yaitu fasies distributary channel dengan pola log cylinder shape, serta terdapat fasies interdistributary channel dan swamp dengan pola log bell shape yang berasosiasi dengan lingkungan pengendapan delta plain. Berdasarkan dari peta ketebalan batubara seam CBM2 diketahui geometri seam CBM 2 pada daerah telitian sekitar 5 – 35 ft dan arah pengendapan seam CBM 2 berarah barat laut – tenggara. Disamping itu Seam CBM 2 ini menebal kaerah tenggara dan menipis kearah barat laut
Analisis karakteristik petrofisik dilakukan dengan melakukan analisis Ultimate dan Proximate yang merupakan analisis yang dilakukan di laboratorium. Setelah mendapatkan hasil dari laboratorium dilakukan analisis dengan membuat crossplot antara parameter petrofisik dari batubara berupa ash, fixed carbon, dan moisture. Dengan mengetahui hasil dari crossplot tersebut maka akan didapatkan beberapa formula yang dapat digunakan untuk menghitung parameter – parameter serta digunakan juga untuk pembuatan model.
Berdasarkan analisis petrofisik didapatkan hasil nilai kandungan ash sebesar 2.68 %, fixed carbon 46.76 %, volatile matter sebesar 41.28 %, moisture sebesar 0.11 %, mean vitrinite reflectance sebesar 0.45 %, total gas content sebesar 127.88 scft/ton dan kalori sebesar 6260 Kcal/kg. Dari hasil analisis petrofisik tersebut maka dapat diketahui bahwa seam CBM 2 ini termasuk dalam jenis batubara bituminous high volatile c menurut ASTM coal rank yang berpotensi sebagi reservoar coalbed methane dan sebagai bahan bakar ekonomis. Berdasarkan hasil overlay peta penyebaran kandungan moisture, peta kedalaman batubara, peta ketebalan batubara, peta fasies batubara dan peta geologi dareha dapat diketahui beberapa area yang berpotensi pada seam CBM 2 lapangan “X”.
v
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN
KATA PENGANTAR i
HALAMAN PERSEMBAHAN iii
SARI iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
BAB I. PENDAHULUAN 1
I.1. Latar Belakang 1
I.2. Batasan Masalah 2
I.3. Maksud dan Tujuan 2
I.4. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 3
I.5. Hasil Penelitian 4
I.6. Manfaat Penelitian 5
BAB II. METODOLOGI PENELITIAN 6
II.1. Tahap Pendahuluan 6
II.2. Sumber Data 7
II.3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 7
II.4. Penulisan Laporan 8
BAB III. TINJAUAN GEOLOGI 10
III.1. Geologi Regional Cekungan Kutai 10
III.2. Stratigrafi Regional Cekungan Kutai 14
BAB IV. DASAR TEORI 18
IV.1. Pengertian Batubara 18
IV.2. Model Geologi untuk Endapan Batubara 20
IV.3. Model Pengendapan Delta Mahakam 24
IV.4. Geometri Lapisan Batubara 30
IV.5. Proses Pembentukan Gas Methane dalam Batubara 33
vi
IV.6. Maseral Pada Batubara 35
IV.7. Data Inti Batuan 36
IV.8. Data Log Sumur 39
IV.9. Korelasi 43
IV.10. Elektofasies 46
BAB V PENYAJIAN DATA 49
V.1 Data Inti Batuan 49
V.2 Data Log Sumur 50
BAB VI HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN 52
VI.1. Analisis Lingkungan Pengendapan 52
VI.2. Analisis Geometri Batubara 58
VI.3. Analisis Petrofisik 62
VI.4. Kalibrasi Data Core ke Data Log 68
VI.5. Analisis Penyebaran Parameter Petrofisik 70
BAB V KESIMPULAN 79
DAFTAR PUSTAKA 81
LAMPIRAN 82
vii
DAFTAR TABEL
Tabel 3.2 Kolom Stratigrafi Cekungan Kutai (Satyana et.all. 1999) 16
Tabel 3.2.1. Kolom Stratigrafi Daerah Telitian (Penulis) 17
Tabel 4.1 Tabel Klasifikasi Batubara Berdasarkan Vitrinite Reflectance
menurut Ward (1984) 19
Tabel 4.2 Tabel Klasifikasi Batubara Berdasarkan ASTM Coal Rank 20
viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.4. Lokasi Daerah Penelitian (dalam Laporan Internal VICO Indonesia) 4
Gambar 2.1. Diagram Alir Penelitian 9
Gambar 3.1 Peta Regional Cekungan Kutei
(modifikasi dari Paterson et al, 1997 dalam Mora 2001) 10
Gambar 3.1.2. Tectonic Setting Cekungan Kutai (Mora et al 2003) 12
Gambar 3.1.2.1. Peta Geologi Daerah Telitian (dalam Laporan Internal VICO
Indonesia) 14
Gambar 4.2.1. Penampang Lingkungan Pengendapan
pada bagian Back Barrier (Horne,1978) 21
Gambar 4.2.2. Penampang Lingkungan Pengendapan pada bagian Lower Delta Plain
(Horne,1978) 22
Gambar 4.2.3. Penampang Lingkungan Pengendapan pada bagian Upper Delta Plain-
Fluvial (Horne,1978) 23
Gambar 4.2.4. Penampang Lingkungan Pengendapan pada bagian Transitional Lower
Delta Plain (Horne,1978) 24
Gambar 4.2.5. Model Lingkungan Pengendapan Batubara di Lingkungan Delta
(J.CHorne et. Al., 1979 ; modifikasi dari Ferm, 1976) 24
Gambar 4.3.1. Morfologi lingkungan pengendapan pada delta (Allen, 1998) 28
Gambar 4.3.2 Model lingkungan pengendapan delta Mahakam (Allen, 1998) 29
Gambar 4.3.3. Pembagian lingkungan pada delta dengan ciri khas endapannya
(Allen et.al, 1998) 29
ix
Gambar 4.5. Proses Pembatubaraan (dalam Coalbed methane characteristics of the
Gates Formation coals, northestern British Columbia: effect of maceral composition,
menurut Lamberson, M.N. and Bustin, R.M., 1993) 34
Gambar 4.6. Klasifikasi Maseral (dalam Part II Coal, Reservoir Issue menurut Crain.E.
R. (Ross),P.Eng, 2010,) 36
Gambar 4.6. Visualisasi Batubara pada Log Sumur 40
Gambar 4.8 Pola Respon dari Log Gamma ray (GR) (Kendall, 2003 modifikasi dari
Emery 1996) 48
Gambar 5.2. Contoh kurva log sumur X-1 51
Gambar 6.1.1 Lingkungan Pengendapan Seam CBM 2 menurut Horne, 1987 52
Gambar 6.1.1.1. Identifikasi pola log sumur X201 berdasarkan
model Horne 1978 53
Gambar 6.1.1.2. Identifikasi pola log sumur X71 berdasarkan
model Horne 1978 53
Gambar 6.1.1.3. Identifikasi pola log sumur X60 berdasarkan
model Horne 1978 54
Gambar 6.1.2.1 Model Lingkungan Pengendapan Menurut Allen (1998) 55
Gambar 6.1.2.2 Korelasi Stratigrafi 55
Gambar 6.1.2.3. Analisis Elektrofasies pada Sumur X201 56
Gambar 6.1.2.4Analisis Elektrofasies pada Sumur X71 56
Gambar 5.1.2.5. Analisis Elektrofasies pada Sumur X60 57
Gambar 6.1.11. Peta fasies batubara seam CBM 2 58
Gambar 6.2.1 Peta Ketebalan Batubara seam CBM 2 59
x
Gambar 6.2.2 Peta Kedalaman Batubara seam CBM 2 60
Gambar.6.2.3 Overlay Peta Ketebalan dan Peta Kedalaman Batubata
Seam CBM 2 61
Gambar.6.3. Crossplot antara Helium Density dengan %Ash 62
Gambar.6.3.2 Crossplot antara density dari log dengan density dari core 63
Gambar.6.3.3. Crossplot antara % Ash dengan RHOB 64
Gambar.6.3.4. Crossplot antara % Ash dengan % Fixed Carbon 65
Gambar.6.3.5. Crossplot antara % Ash dengan % Moisture 65
Gambar.6.3.6. Crossplot antara % Ash dengan % Volatile Matter 66
Gambar.6.3.7. Crossplot antara % Ash dengan % Semua Parameter ( Fixed Carbon,
Moisture dan Volatile Matter) 67
Gambar.6.3.8. Crossplot antara % Total Gas Content
dengan % Mean Vitrinite Reflectance 68
Gambar 6.4.1.Kalibrasi Data Core ke Data Log 69
Gambar.6.5.1.Peta Penyebaran Batubara dan Nonbatubara 70
Gambar.6.5.2.Model Penyebaran Kandungan Ash 71
Gambar.6.5.2.1.Peta Penyebaran Kandungan Ash 72
Gambar.6.5.3.Model Penyebaran Kandungan Fixed Carbon 73
Gambar.6.5.3.1.Peta Penyebaran Kandungan Fixed Carbon 74
Gambar.6.5.4.Model Penyebaran Kandungan Moisture 75
Gambar.6.5.4.1.Peta Penyebaran Kandungan Moisture 76
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Batubara adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, berasal dari tumbuh-
tumbuhan (komposisi utamanya karbon, hidrogen, dan oksigen), berwarna coklat
sampai hitam, sejak pengendapannya terkena proses kimia dan fisika yang
mengakibatkan terjadinya pengkayaan kadungan karbonnya (Wolf,1984, dalam
Kuncoro, 1996).
Di alam kondisi kualitas batubara dijumpai sangat bervariasi, baik secara
vertikal maupun lateral, antara lain bervariasinya kandungan sulfur dan sodium,
kondisi roof dan floor, kehadiran parting dan pengotor, proses leaching. Kondisi
tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembentukan batubara yang kompleks,
lingkungan pengendapan yang khas sebagai tempat terbentuknya batubara dan
proses-proses geologi yang berlangsung bersamaan atau setelah batubara terbentuk
(Kuncoro, 1996).
Kualitas batubara ditentukan oleh lingkungan pengendapan, aspek fisika, kimia, dan
biologi, yang akan mempengaruhi besarnya kandungan komponen penting dalam batubara
antara lain ash, fixed carbon, moisture, volatile matter, dan vitrinite reflectance kandungan
dari unsur – unsur tersebut mempengaruhi dalam besarnya kalori dan total gas content
dalam batubara. Kandungan komponen – komponen tersebut sangat penting dalam
mengetahui kualitas batubara.
Batubara yang terbentuk di lingkungan back barrier mempunyai kandungan sulfur
tinggi (>1%), demikian juga dengan di lingkungan lower delta plain kandungan sulfurnya
agak tinggi (0.7 % -1 %). Berbeda dengan yang terbentuk di lingkungan upper delta plain
yang kandungan sulfurnya rendah (0.1 % - 0.7 %). Suplai sulfat lebih banyak dari air laut
daripada air sungai, sehingga reaksi lebih mudah terjadi pada batubara yang berasosiasi
dengan kondisi marine.
2
Batubara menjadi sangat penting dan perlu dipelajari karena merupakan salah satu aspek
penting dalam usaha mengembangkan kegiatan penambangan batubara sebagai penggerak
roda ekonomi dan pegembangan batubara sebagai sumber energi baru yaitu sebagai
reservoar coalbed methane. Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian
mengenai hubungan antara kualitas batubara dengan lingkungan pengendapan pembentuk
batubara dengan judul “Analisis Fasies dan Karakteristik Pertrofisik Batubara Seam CBM 2,
Formasi Balikpapan, Lapangan “X”, Cekungan Kutai, Berdasarkan Data Log Sumur dan Inti
Batuan”.
I.2. Batasan Masalah
Pembahasan penelitian ini dibatasi pada :
1. Bagaimana lingkungan pengendapan batubara seam CBM2, Formasi
Balikpapan, Cekungan Kutai di daerah studi berdasarkan atas data
data log sumur dan inti batuan?
2. Bagaimana geometri lapisan batubara pada lapangan “X’, seam
CBM2, Formasi Balikpapan, Cekungan Kutai?
3. Bagaimana karekteristik petrofisik batubara pada lapangan “X”, seam
CBM2, Formasi Balikpapan, Cekungan Kutai?
4. Bagaimana penyebaran lapisan reservoar yang berpotensi pada
lapangan “X”, seam CBM2, Formasi Balikpapan, Cekungan Kutai?
Permasalahan ini diharapkan dapat dipecahkan dalam penelitian ini untuk
memberi nilai tambah dalam pengembangan lapangan selanjutnya.
I.3. Maksud dan Tujuan Penelitian
Maksud dari penelitian skripsi ini adalah untuk menerapkan ilmu yang telah
didapatkan di bangku kuliah dalam praktek yang sebenarnya di lapangan kerja.
Diharapkan tercapai kesinambungan antara teori dengan pengalaman kerja yang
didapatkan dari perusahaan serta merupakan salah satu syarat yang wajib
dilaksanakan dalam memenuhi persyaratan Sarjana Strata-1 pada Program Studi
Teknik Geologi, Fakultas Teknologi Mineral, UPN “Veteran” Yogyakarta.
3
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Mengetahui lingkungan pengendapan batubara seam CBM2, Formasi
Balikpapan, Cekungan Kutai di daerah studi berdasarkan atas data log sumur
dan inti batuan.
2. Mengetahui geometri lapisan batubara pada lapangan “X”, seam CBM 2,
Formasi Balikpapan, Cekungan Kutai.
3. Mengetahui karekteristik petrofisik batubara pada lapangan “X”, seam
CBM2, Formasi Balikpapan, Cekungan Kutai.
4. Mengetahui penyebaran lapisan reservoar yang berpotensi pada lapangan
“X”, seam CBM2, Formasi Balikpapan, Cekungan Kutai.
I. 4. Lokasi dan Waktu Penelitian
Tahap pengumpulan dan analisis data dalam tugas akhir ini dilaksanakan
selama kurang lebih tiga bulan, yaitu mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Mei
2011 yang dilanjutkan dengan penyusunan karya tulis tugas akhir. Sedangkan untuk
pengambilan dan pengolahan data, dilaksanakan di VICO Indonesia. Fokus kajian
tugas akhir ini yaitu pada lapangan “X”, Cekungan Kutai, Kalimantan Timur
(Gambar I.4).
4
Gambar 1.4. Lokasi Daerah Penelitian ( dalam Laporan Internal VICO Indonesia)
I.5. Hasil Penelitian
Dengan melakukan skripsi ini yang berjudul “Analisis Fasies Batubara dan
Karakteristik Petrofisik Formasi Balikpapan, Lapangan “X”, Cekungan Kutai
Berdasarkan Data Log Sumur dan Inti Batuan”, diharapkan hasil telitian yang
didapatkan adalah :
1. Kalibrasi data core dan data log sumur seam CBM2
2. Model penyebaran parameter batubara seam CBM2
5
3. Interpretasi daerah potensial untuk eksplorasi coalbed methane dan daerah
yang potensial untuk eksplorasi batubara sebagai bahan bakar yang
ekonomis.
4. Interpretasi fasies dan lingkungan pengendapan seam CBM2
I.6 Manfaat Penelitian
Manfaat keilmuan yang didapatkan adalah :
1. Penelitian ini dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk
menerapkan ilmu geologi secara langsung di dunia industri minyak dan
gas, sehingga mahasiswa mengetahui cara dan langkah kerja nyata dalam
pengintegrasian data untuk memberikan hasil analisis yang maksimal.
2. Mahasiswa mampu berfikir secara deskriptif, serta mampu menjawab dan
menyelesaikan persoalan di lapangan, sehingga dapat menerapkan dan
mengembangkan pengetahuan yang diperoleh di perguruan tinggi,
terutama penerapan ilmu geologi di dalam dunia industri minyak dan gas.
3. Membantu memecahkan permasalahan geologi yang berhubungan dengan
analisis dan intepretasi data bawah permukaan daerah telitian.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi VICO
Indonesia untuk pengembangan Lapangan “X” sehingga dapat
mengoptimalkan hasil produksi pada” dan dapat memberikan gambaran
peta lokasi yang prospek pada Lapangan “X”.
6
BAB II
METODOLOGI PENELITIAN
Metode yang digunakan adalah pemetaan distribusi reservoar secara vertikal
dan lateral dengan mengintegrasikan data log sumur dan data inti batuan dengan
pendekatan sikuen stratigrafi.
Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka dilakukan empat tahap
utama dalam penelitian ini, meliputi tahap pendahuluan, tahap pengumpulan data,
tahap pengolahan dan analisis data, dan tahap penyusunan laporan.
II.1 Tahap Pendahuluan
Tahap pendahuluan ini adalah merupakan tahap persiapan yang dilakukan
penulis sebelum melakukan penelitian atau analisis data. Pada tahap pendahuluan hal
– hal yang dilakukan antara lain :
1. Penyusunan proposal penelitian serta kelengkapan administrasi
Pada tahap ini dilakukan dengan maksud melihat kesiapan mahasiswa
sebelum melakukan penelitian dan sesuai dengan peraturan atau ketentuan
yang telah dibuat oleh Jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknologi
Mineral, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
2. Kajian pustaka
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan gambaran
geologi daerah penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran
secara regional maupun lokal keadaan geologi daerah secara umum.
Termasuk pengumpulan dan pembahasan literatur-literatur Lapangan “X”
terdahulu.
7
3. Pengumpulan data yang akan dianalisis
Pengumpulan data berupa data sumur, data inti batuan, maupun data lain
yang menunjang penelitian.
II.2 Sumber Data
Data yang digunakan dalam melakukan peneletian meliputi data primer dan
data sekunder. Adapun data primer meliputi :
a. Data log sumur digunakan untuk studi sikuen stratigrafi, analisis fasies dan
perhitungan petrofisik yang dikombinasikan dengan hasil analisis fasies
dan hasil analisis proximate yang berupa perhitungan kandungan ash, fixed
carbon, moisture dan volatile matter dari data inti bor.
Sedangkan untuk data sekunder meliputi :
a. Penelitian terdahulu tentang geologi regional Cekungan Kutai dan
Lapangan Mutiara
b. Data diskripsi dan analisis inti bor untuk identifikasi fasies pengendapan,
lingkungan pengendapan, analisis volume Ash, Fixed Carbon, Moisture,
dan Volatile matter.
II.3 Pengolahan dan Analisis Data
Pada tahapan ini dilakukan analisis geometri dan kualitas reservoar.
Reservoar yang menjadi target penelitian adalah reservoar seam CBM 2 pada
Formasi Balikpapan.
Perangkat lunak pendukung yang digunakan yaitu :
a. Elan digunakan untuk analisis tiap sumur, antar sumur dan kalibrasi
data core dan data log sumur.
b. Petrel digunakan untuk membuat korelasi data log sumur, pembuatan
model pengendapan batubara dan non batubara, dan model
penyebaran parameter – parameter petrofisik batubara.
8
Tahapan ini secara garis besar mencakup beberapa tahap pengerjaan, yaitu:
a. Analisis data log sumur dan data batuan inti serta perhitungan
parameter petrofisik.
b. Korelasi antar sumur secara detil dan terbatas berdasarkan fasies
pengendapan.
c. Pembuatan model fasies pengendapan batubara dan model penyebaran
parameter – parameter petrofisik batubara.
Urut-urutan pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada diagram alir berikut.
(Gambar2.1.).
II.4. Penulisan Laporan
Tahap akhir dari penelitian ini adalah penyajian data dan hasil akhir dari
penelitian yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan gambar. Tulisan dan gambar
tersebut diintegrasikan dalam bentuk laporan skripsi.
10
BAB III
TINJAUAN GEOLOGI
III.1 Geologi Regional Cekungan Kutai
Cekungan Kutai dibatasi oleh Paternoster platform, Barito Basin, dan
Pegunungan Meratus ke selatan, dengan Schwaner Blok ke barat daya, lalu Tinggian
Mangkalihat di sebelah utara - timur laut, dan Central Kalimantan Mountains (Moss
dan Chambers, 1999) untuk barat dan utara (Gambar 3.1.1). Cekungan Kutai
memiliki sejarah yang kompleks (Moss et al., 1997), dan merupakan satu-satunya
cekungan Indonesia yang telah berevolusi dari internal rifting fracture/foreland basin
ke marginal-sag.. Sebagian besar produk awal pengisi Cekungan Kutai telah terbalik
dan diekspos (Satyana et al., 1999), pada Miosen Tengah sampai Miosen Akhir
sebagai akibat dari terjadinya tumbukan / kolusi block Micro Continent. Dari
peristiwa ini menyebabkan adanya pengangkatan cekungan, perubahan sumbu
antiklin dan erosi permukaan yang mengontrol sedimentasi pada Delta Mahakam.
Delta Mahakam terbentuk di mulut sungai Mahakam sebelah timur pesisir pulau
Kalimantan. Dengan garis pantainya berorientasi arah NE-SW dan dibatasi oleh Selat
Makasar, selat yang memisahkan pulau Kalimantan dan Sulawesi.
Gambar 3.1 Peta Regional Cekungan Kutei
(modifikasi dari Paterson et al, 1997 dalam Mora 2001)
Lokasi telitian
11
III.1.1 Tatanan Tectonic Cekungan Kutai
Tatanan tectonic cekungan kutai dapat diringkas sebagai berikut (Gambar 3.1.2).
• Awal Synrift (Paleosen ke Awal Eosen): Sedimen tahap ini terdiri dari
sedimen aluvial mengisi topografi NE-SW dan NNE-SSW hasil dari trend
rifting di Cekungan Kutai darat. Mereka menimpa di atas basemen kompresi
Kapur akhir sampai awal Tersier berupa laut dalam sekuen.
• Akhir Synrift (Tengah sampai Akhir Eosen): Selama periode ini, sebuah
transgresi besar terjadi di Cekungan Kutai, sebagian terkait dengan rifting di
Selat Makassar, dan terakumulasinya shale bathial sisipan sand.
• Awal Postrift (Oligosen ke Awal Miosen): Selama periode ini, kondisi bathial
terus mendominasi dan beberapa ribu meter didominasi oleh akumulasi shale.
Di daerah structural shallow area platform karbonat berkembang
• Akhir Postrift (Miosen Tengah ke Kuarter): Dari Miosen Tengah dan
seterusnya sequence delta prograded secara major berkembang terus ke laut
dalam Selat Makassar, membentuk sequence Delta Mahakam, yang
merupakan bagian utama pembawa hidrokarbon pada cekungan. Berbagai
jenis pengendapan delta on – dan offshore berkembang pada formasi
Balikpapan dan Kampungbaru, termasuk juga fasies slope laut dalam dan
fasies dasar cekungan. Dan juga hadir batuan induk dan reservoir yang sangat
baik dengan interbedded sealing shale. Setelah periode ini, proses erosi ulang
sangat besar terjadi pada bagian sekuen Kutai synrift.
12
Gambar 3.1.2. Tectonic Setting Cekungan Kutai (Mora et al 2003)
III.1.2. Struktur Geologi Regional Cekungan Kutai
Seperti halnya beberapa cekungan di Asia Tenggara lainnya, half graben
terbentuk selama Eosen sebagai akibat dari fase ekstensional atau pemekaran
regional (Allen dan Chambers, 1998). Pemekaran ini merupakan manifestasi
tumbukan sub lempeng Benua India dengan lempeng Benua Asia yang memacu
pemekaran di sepanjang rangkaian strike-slip fault dengan arah baratlaut-tenggara
(NW-SE) yang merupakan reaktifasi struktur sebelumnya, yaitu sesar Adang- Lupar
dan sesar Mangkalihat.
Cekungan ini mulai terisi endapan sedimen transgresif pada kala Eosen
Akhir hingga Oligosen. Kemudian diikuti oleh sekuen regresif pada kala Miosen
Awal yang merupakan inisiasi kompleks Delta Mahakam saat ini. Proses progadasi
Delta Mahakam meningkat dengan sangat signifikan pada kala Miosen Tengah, yaitu
ketika tinggian Kuching di bagian Barat terangkat dan inversi pertama terjadi.
Progradasi tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Inversi Kedua terjadi pada
13
masa Mio-Pliosen, ketika bagian lempeng Sula-Banggai menabrak Sulawesi dan
menghasilkan mega shear Palu-Koro.
Pembentukan dan perkembangan struktur utama yang mengontrol sub
Cekungan Kutai Bawah erat kaitannya dengan proses tektonik Inversi Kedua, yaitu
struktur-struktur geologi dengan pola kelurusan arah timurlaut-baratdaya (NNE-
SSW). Menurut Allen dan Chambers, (1998) pola ini dapat terlihat pada struktur
umum yang tersingkap di Cekungan Kutai saat ini, yaitu berupa jalur sesar-sesar
anjakan dan kompleks rangkaian antiklin/antiklinorium.
Perkembangan struktur lainnya adalah pola kelurusan berarah
baratlauttenggara (NW-SE), berupa sesar-sesar normal yang merupakan manifestasi
pelepasan gaya utama yang terbentuk sebelumnya. Sesar-sesar ini terutama berada di
bagian utara cekungan, memotong sedimen berumur Miosen Tengah dan bagian lain
yang berumur lebih tua.
II.1.2.1 Struktur Geologi Daerah Telitian
Struktur geologi yang berkembang di daerah telitian adalah perlipatan antiklin.
Perlipatan antiklin ini berarah relatif utara timur laut – selatan barat daya, hal tersebut
dapat diketahui berdasarkan dari kenampakan pada peta geologi daerah telitian
(Gambar 3.1.2.1), serta laporan internal VICO indonesia. Pola-pola struktur yang
berkembang pada daerah telitian mengikuti pola struktur Cekungan Kutai yaitu pola
anticlinorium yang berarah relatif utara timur laut – selatan barat daya. Struktur pada
daerah telitian dikontrol oleh gaya kompresi pada Cekungan Kutai yang berhubungan
dengan pemekaran lantai samudra (sea floor spreading) di selat Makasar pada akhir
Tersier.
14
Gambar 3.1.2.1. Peta Geologi Daerah Telitian (dalam Laporan Internal VICO Indonesia)
II.2. Stratigrafi Regional Cekungan Kutai
Satyana et all, 1999 dalam An Outline Of The Geology Of Indonesia, 2001
melakukan penelitian dan menyusun stratigrafi Cekungan Kutai dari tua ke muda
sebagai berikut :
1. Formasi Beriun
Formasi Beriun terdiri dari batulempung, selang seling batupasir dan
batugamping. Formasi Beriun berumur Eosen Tengah – Eosen Akhir dan
diendapkan dalam lingkungan fluviatil hingga litoral.
2. Formasi Atan
Diatas Formasi Beriun terendapkan Formasi Atan yang merupakan hasil dari
pengendapan setelah terjadi penurunan cekungan dan pengendapan pada
15
Formasi Beriun. Formasi Atan terdiri dari batugamping dan batupasir kuarsa.
Formasi Atan berumur Oligosen Awal.
3. Formasi Marah
Formasi Marah Diendapakan secara selaras diatas Formasi Atan. Formasi
Marah terdiri dari batulempung, batupasir kuarsa dan batugamping berumur
Oligosen Akhir.
4. Formasi Pamaluan
Diendapkan pada kala Miosen Awal hingga Miosen Akhir di lingkungan
neritik, dengan ciri litologi batulempung, serpih, batugamping, batulanau dan
sisipan batupasir kuarsa. Formasi ini diendapkan dalam lingkungan delta
hingga litoral.
5. Formasi Bebulu
Diendapkan pada kala Miosen Awal hingga Miosen Tengah di lingkungan
neritik. Ciri litologi Formasi Bebulu adalah batugamping.
6. Formasi Pulubalang
Formasi Pulubalang diendapkan selaras di atas Formasi Pamaluan, terdiri dari
atas selang-seling pasir lanauan dengan disipan batugamping tipis dan
batulempung. Umur dari formasi ini adalah Miosen Tengah dan diendapkan
pada lingkungan sub litoral, kadang-kadang dipengaruhi oleh marine influx.
Formasi ini mempunyai hubungan menjari dengan Formasi Bebulu yang
tersusun oleh batugamping pasiran dengan serpih.
7. Formasi Balikpapan
Formasi Balikpapan diendapkan secara selaras di atas Formasi Pulubalang.
Formasi ini terdiri dari selang seling antara batulempung dan batupasir
dengan sisipan batubara dan batugamping di bagian bawah. Data pemboran
yang pernah dilakukan di Cekungan Kutai membuktikan bahwa Formasi
Balikpapan diendapkan dengan sistem delta, pada delta plain hingga delta
front. Umur formasi ini Miosen Tengah – Miosen Akhir.
8. Formasi Kampungbaru
Formasi Kampung Baru ini berumur Mio-Pliosen, terletak di atas Formasi
Balikpapan, terdiri dari selang-seling batupasir, batulempung dan batubara
16
dengan disipan batugamping tipis sebagai marine influx. Lingkungan
pengendapan formasi ini adalah delta.
9. Formasi Mahakam
Formasi Mahakam terbentuk pada kala Pleistosen – sekarang. Proses
pengendapannya masih berlangsung hingga saat ini, dengan ciri litologi material
lepas berukuran lempung hingga pasir halus.
Tabel 3.2 Kolom Stratigrafi Cekungan Kutai (Satyana et all. 1999)
17
III.2.1. Stratigrafi Daerah Telitian
Secara regional, daerah penelitian termasuk pada Formasi Balikpapan.
Formasi Balikpapan terdiri dari beberapa formasi, yaitu Formasi Mentawir, Formasi
Maruat, dan Formasi Klandasan. Formasi Balikpapan diendapkan pada Kala Miosen
tengah.
Pada derah telitian ini terdapat Formasi Balikpapan tersusun atas litologi
dominan batupasir yang berselingan dengan litologi batulempung dan perlapisan
batubara ( Tabel 2.2.1).
Tabel 3.2 Kolom Stratigrafi Daerah Telitian (Penulis)
18
BAB IV
DASAR TEORI
Dasar teori berisi tentang pengertian dan pengetahuan dasar mengenai data-
data yang digunakan dalam penelitian. Serta berisi tentang teori yang berhubungan
dengan studi fasies dan karakteristik petrofisik batubara.
IV.1. Pengertian Batubara
Secara umum batubara dapat diartikan sebagai bahan bakar hidrokarbon yang
terbentuk dari tumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen dan terkena pengaruh
panas serta tekanan yang berlangsung lama sekali. Secara garis besar batubara terdiri
dari zat organik, air dan bahan mineral. Batubara dapat diklasifikasikan menurut
tingkatan yaitu lignit, sub bituminous, bituminous dan antrasit (Tabel 4.1, 4.2).
Penyebaran endapan batubara di Indonesia cukup meluas baik di Indonesia
bagian barat maupun Indonesia bagian timur. Kebanyakan terdapat di cekungan-
cekungan batubara pada beberapa tempat di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan,
seperti Cekungan Sumatera Selatan, Cekungan Kutai, Cekungan Barito dan
sebagainya.
Definisi batubara dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu sifat fisiknya, asal
kejadiannya, dan pemanfaatannya. Untuk memberikan gambaran mengenai
pengertian batubara secara umum oleh beberapa penulis dapat diuraikan sebagai
berikut :
1) Thiessen (1947) mendefinisikan batubara sebagai berikut :
Batubara adalah suatu benda padat yang kompleks, terdiri dari bermacam-
macam unsur yang mewakili banyak komponen kimia, dimana hanya sedikit dari
komponen kimia tersebut yang dapat diketahui. Pada umumnya benda padat
19
tersebut homogen, tetapi hampir semua berasal dari sisa-sisa tumbuhan. Sisa-sisa
tumbuhan tersebut sangat kompleks, terdiri dari berbagai macam tissue dimana
setiap tissue terdiri dari beberapa sel. Dengan sendirinya akan berkomposisi
sejumlah komponen kimia dalam perbandingan yang bervariasi. Jadi dapat
disimpulkan bahwa batubara adalah suatu benda padat organik yang mempunyai
komposisi kimia yang sangat rumit.
2). Wolf (1984)
Batubara adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, berasal dari tumbuh-
tumbuhan (komposisi utamanya karbon, hidrogen, dan oksigen), berwarna coklat
sampai hitam, sejak pengendapannya terkena proses kimia dan fisika yang
mengakibatkan terjadinya pengkayaan kadungan karbonnya.
Dari kedua definisi yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil suatu
rangkuman pengertian batubara adalah suatu karbonat berlapis yang terbentuk oleh
akumulasi sisa-sisa tumbuhan bersama hasil dekomposisinya yang terawetkan dalam
lapisan sedimen dan menjadi kaya akan unsur karbon dengan adanya proses
diagenesis.
Tabel 4.1 Tabel Klasifikasi Batubara Berdasarkan Vitrinite Reflectance menurut Ward (1984)
20
Tabel 4.2 Tabel Klasifikasi Batubara Berdasarkan ASTM Coal Rank
IV.2. Model Geologi untuk Pengendapan Batubara
Model geologi untuk pengendapan batubara menerangkan hubungan antara
genesa batubara dan batuan sekitarnya baik secara vertikal maupun lateral pada suatu
cekungan pengendapan dalam kurun waktu tertentu.
IV.2.1 Lingkungan Pengendapan dan Fasies Batubara
Identifikasi bermacam lingkungan pengendapan ditunjukkan oleh semua
komponen sistem pengendapan dan letak lapisan batubara pada lingkungan modern
berdasarkan studi lingkungan pengendapan dengan didukung data dari tambang
batubara, pemboran, dan profil singkapan.
a. Lingkungan Pengendapan Barrier
Ke arah laut batupasir butirannya semakin halus dan berselang seling
dengan serpih gampingan merah kecoklatan sampai hijau. Batuan karbonat
dengan fauna laut ke arah darat bergradasi menjadi serpih berwarna abu-abu
gelap sampai hijau tua yang mengandung fauna air payau. Batupasir pada
lingkungan ini lebih bersih dan sortasi lebih baik karena pengaruh gelombang
dan pasang surut.
21
b. Lingkungan Pengendapan Back-Barrier
Lingkungan ini terutama disusun oleh urutan perlapisan serpih abu-
abu gelap kaya bahan organik dan batulanau yang terus diikuti oleh batubara
yang secara lateral tidak menerus dan zona siderit yang berlubang. Lingkungan
back barrier : batubaranya tipis, pola sebarannya memanjang sejajar sistem
penghalang atau sejajar jurus perlapisan, bentuk lapisan melembar karena
dipengaruhi tidal channel setelah pengendapan atau bersamaan dengan proses
pengendapan dan kandungan sulfurnya tinggi.
Gambar 4.2.1. Penampang Lingkungan Pengendapan pada bagian Back Barrier (Horne,1978)
c. Lingkungan Pengendapan Lower Delta Plain
Endapan yang mendominasi adalah serpih dan batulanau yang mengkasar ke
atas. Pada bagian bawah dari teluk terisi oleh urutan lempung-serpih abu-abu
gelap sampai hitam, kadang-kadang terdapat mudstone siderit yang
penyebarannya tidak teratur. Pada bagian atas dari sekuen ini terdapat batupasir
dengan struktur ripples dan struktur lain yang ada hubungannya dengan arus. Hal
ini menunjukkan bertambahnya energi pada perairan dangkal ketika teluk terisi
endapan yang mengakibatkan terbentuk permukaan dimana tanaman
menancapkan akarnya, sehingga batubara dapat terbentuk. Lingkungan lower
delta plain: batubaranya tipis, pola sebarannya umumnya sepanjang channel atau
jurus pengendapan, bentuk lapisan ditandai oleh hadirnya splitting oleh endapan
crevase splay dan kandungan sulfurnya agak tinggi.
22
Gambar 4.2.2. Penampang Lingkungan Pengendapan pada bagian Lower Delta Plain
(Horne,1978)
d. Lingkungan Pengendapan Upper Delta Plain-Fluvial
Endapan didominasi oleh bentuk linier tubuh batupasir lentikuler dan pada
bagian atasnya melidah dengan serpih abu-abu, batulanau, dan lapisan batubara.
Mineral batupasirnya bervariasi mulai dari lithic greywackearkose, ukuran butir
menengah sampai kasar. Di atas bidang gerus terdapat kerikil lepas dan hancuran
batubara yang melimpah pada bagian bawah, makin ke atas butiran menghalus
pada batupasir. Dari bentuk batupasir dan pertumbuhan point bar menunjukkan
bahwa hal ini dikontrol oleh meandering. Endapan levee dicirikan oleh sortasi
yang buruk, perlapisan batupasir dan batulanau yang tidak teratur hingga
menembus akar. Ketebalannya bertambah apabila mendekati channel dan
sebaliknya. Lapisan pembentuk endapan alluvial plain cenderung lebih tipis
dibandingkan endapan upper delta plain. Lingkungan upper delta plain – fluvial:
batubaranya tebal dapat mencapai lebih dari 10 m, sebarannya meluas cenderung
memanjang sejajar jurus pengendapan, tetapi kemenerusan secara lateral sering
23
terpotong channel, bentuk batubara ditandai hadirnya splitting akibat channel
kontemporer dan washout oleh channel subsekuen dan kandungan sulfurnya
rendah.
Gambar 4.2.3. Penampang Lingkungan Pengendapan pada bagian Upper Delta Plain-Fluvial
(Horne,1978)
e. Lingkungan Pengendapan Transitional Lower Delta Plain
Zona diantara lower dan upper delta plain dijumpai zona transisi yang
mengandung karakteristik litofasies dari kedua sekuen tersebut. Disini sekuen
bay fill tidak sama dengan sekuen upper delta plain ditinjau dari kandungan
fauna air payau sampai marin serta struktur burrowed yang meluas. Endapan
channel menunjukkan kenampakan migrasi lateral lapisan piont bar accretion
menjadi channel pada upper delta plain. Channel pada transitional delta plain ini
berbutir halus daripada di upper delta plain, dan migrasi lateralnya hanya satu
arah. Levee berasosiasi dengan channel yang menebal dan menembus akar secara
meluas daripada lower delta plain. Batupasir tipis crevasse splay umum terdapat
pada endapan ini, tetapi lebih sedikit banyak daripada di lower delta plain namun
tidak sebanyak di upper delta plain. Lingkungan transitional lower delta plain :
batubaranya tebal dapat lebih dari 10 m, tersebar meluas cenderung memanjang
jurus pengendapan, tetapi kemenerusan secara lateral sering terpotong channel,
24
bentuk lapisan batubara ditandai splitting akibat channel kontemporer dan
washout oleh channel subsekuen dan kandungan sulfurnya agak rendah.
Gambar 4.2.4. Penampang Lingkungan Pengendapan pada bagian Transitional Lower Delta
Plain (Horne,1978)
Gambar 4.2.5. Model lingkungan pengendapan batubara di lingkungan delta (J.CHorne et. Al.,
1979 ; modifikasi dari Ferm, 1976)
VI.3. Model Pengendapan Delta Mahakam
Delta merupakan garis pantai yang menjorok ke laut, terbentuk oleh adanya
sedimentasi sungai yang memasuki laut, danau atau laguna dan pasokan sedimen
lebih besar daripada kemampuan pendistribusian kembali oleh proses yang ada pada
25
cekungan pengendapan (Elliot, 1986 dalam Allen, 1997) Menurut Boggs, 1987
(Dalam Allen, 1998), delta diartikan sebagai suatu endapan yang terbentuk oleh
proses sedimentasi fluvial yang memasuki tubuh air yang tenang (Gambar 4.3.2).
Dataran delta menunjukkan daerah di belakang garis pantai dan dataran delta bagian
atas (Upper Delta Plain) didominasi oleh proses sungai dan dapat dibedakan oleh
pengaruh laut terutama penggenangan tidal. Delta terbentuk karena adanya suplai
material sedimentasi dari sistem fluvial. Ketika sungai – sungai pada sistem fluvial
tersebut, terbentuk pula morfologi delta yang khas dan dapat dikenali pada setiap
sistem yang ada. Morfologi delta secara umum terdiri dari tiga yaitu : delta plain,
delta front dan prodelta (Gambar 4.3.1)
VI.3.1. Delta Plain
Menurut Allen (1998) Delta plain merupakan bagian delta yang terdiri dari
channel yang sudah ditinggalkan. Delta plain merupakan bagian dataran dari delta
dan terdiri atas endapan sungai yang lebih dominan daripada endapan laut dan
membentuk suatu dataran rawa – rawa yang didominasi oleh material sedimen
berbutir halus, seperti serpih organik dan batubara. Pada kondisi iklim yang
cenderung kering (semi-arid), sedimen yang terbentuk didominasi oleh lempung dan
evaporit. Dataran delta plain tersebut digerus oleh channel pensuplai material
sedimen dan membentuk suatu percabangan. Gerusan – gerusan tersebut biasanya
mencapai kedalaman 5 – 10 meter dan menggerus sampai pada sedimen delta front.
Sedimen pada channel tersebut disebut sandy channel dan membentuk distributary
channel yang dicirikan oleh batupasir lempungan. Sublingkungan delta plain dibagi
menjadi :
VI.3.1.1 Upper Delta Plain
Menurut Allen (1998), upper delta plain terbentuk diatas area tidal
atau laut dan endapannya secara umum terdiri dari :
1. Endapan distributary channel
Endapan distributary channel terdiri dari endapan braded dan meandering
levee dan endapan point bar. Endapan distributary channel ditandai dengan
26
adanya bidang erosi pada bagian dasar urutan fasies dan menunjukkan
kecenderungan menghalus ke atas. Struktur sedimen yang umum dijumpai
adalah cross bedding, ripple cross stratification scoure and fill dan lensa –
lensa lempung. Endapan point bar terbentuk apabila terputus dari
channelnya. Sedangkan levee alami berasosiasi dengan distributary channel
sebagai tanggul alam yang memisahkan dengan interdistibutary channel.
Sedimen pada bagian ini berupa pasir halus dan rombakan material organik
serta lempung yang terbentuk sebagai hasil luapan material selama terjadinya
banjir.
2. Lacustrine delta fill dan endapan interdistributary flood plain
Endapan interdistributary channel merupakan endapan yang diantara
distributary channel. Lingkungan ini mempunyai kecepatan arus paling kecil,
dangkal, tidak berelief dan proses akumulasi sedimen lambat. Pada
interdistributary channel dan flood plain area terbentuk suatu endapan yang
berukuran lanau samapi lempung yang sangat dominan. Struktur sedimennya
adalah laminasi sejajar dan burrowing structure endapan pasir yang bersifat
lokal, tipis dan kadang banjir sebagai pengaruh gelombang.
VI.3.1.2. Lower Delta Plain
Lower delta plain terletak pada daerah dimana terjadi interaksi antara
sungai dengan laut, yaitu low tidemark sampai batas kehadiran yang
dipengaruhi pasang–surut. Litologinya didominasi oleh urutan serpih dan
batulanau yang mengkasar kearah atas. Pada bagian bawah terisi oleh urutan
lempung-serpih yang merupakan litologi dominan, kadang – kadang terdapat
batugamping dan mudstone siderit yang sebenaryna tidak teratur. Pada bagian
atas terdapat batupasir dengan struktur ripple dan struktur lain yang
berhubungan dengan arus, hal ini menunjukkan bertambahnya energi pada
perairan dangkal ketika teluk terisi endapan. Umunya daerah ini mengandung
fosil laut (moluska) atau air payau dan struktur burrow. Fosil – fosil ini
biasanya melimpah di bagian bawah serpih-lempung (Allen, 1998)
27
VI.3.2. Delta Front
Menurut Allen (1998) Delta front merupakan sublingkungan dengan energi
yang tinggi dan sedimen secara tetap dipengaruhi oleh adanya proses pasang-surut,
arus laut sepanjang pantai dan aksi gelombang. Delta front terbentuk pada
lingkungan laut dangkal dan akumulasi sedimennya berasal dari distributary
channel. Batupasir yang diendapkan dari distributary channel tersebut membentuk
endapan bar yang berdekatan dengan teluk atau mulut distributary channel tersebut.
Pada penampang stratigarfi, endapan bar tersebut memperlihatkan distribusi butiran
mengkasar ke atas dalam skala yang besar dan menunjukkan perubahan fasies secara
vertikal ke atas, mulai dari endapan lepas pantai atau prodelta yang berukuran butir
halus ke fasies garis pantai yang disominasi batupasir. Diantara bar dan mulut
distributary channel akan terakumulasi lempung lanauan atau lempung pasiran dan
bergradasi menjadi lempung ke arah laut.
Menurut Coleman (1969) dan Fisher (1969) dalam Galloway (1990),
lingkungan pengendapan delta front dapat dibagi menjadi beberapa sublingkungan
dengan karakteristik asosiasi fasies yang berbeda, yaitu :
1. Subaqueous Levees
Merupakan kenampakan fasies endapan delta front yang berasosiasi dengan
active channel mouth bar. Fasies ini sulit untuk didentifikasi dan dibedakan
dengan fasies lainnya pada endapan delta masa lampau.
2. Channel
Channel ditandai dengan adanya bidang erosi pada bagian dasar urutan fasies
dan menghalus ke atas. Struktur sedimen yang umumnya dijumpai adalah
cross bedding, ripple cross stratification scoure and fill.
3. Distributary Mouth Bar
Pada lingkungan ini terjadi pengendapan dengan kecepatan yang paling tinggi
dalam sistem pengendapan delta. Sedimen umumnya tersusun atas pasir yang
diendapkan melalui proses fluvial. Struktur sedimen yang dapat dijumpai
antara lain : current ripple, cross bedding dan massive graded bedding.
28
4. Distal Bar
Pada distal bar, urutan fasies cenderung menghalus ke atas, umumnya
tersusun atas pasir halus. Struktur sedimen yang umumnya dijumpai antara
lain : laminasi, perlapisan silang siur tipe through.
VI.3.3 Prodelta
Prodelta merupakan sublingkungan transisi antara delta front dan endapan
normal marine shelf yang berada di laur delta front. Prodelta merupakan kelanjutan
delta front ke arah laut dengan perubahan litologi dari batupasir bar ke endapan
batulempung dan selalu ditandai oleh zona lempungan tanpa pasir. Daerah ini
merupakan bagian distal dari delta, dimana hanya terdiri dari akumulasi lanau dan
lempung dan biasanya sendiri serta fasies mengkasar ke atas memperlihatkan transisi
dari lempungan prodelta ke fasies yang lebih batupasir dari delta front. Litologi dari
prodelta ini banyak ditemukan bioturbasi yang merupakan karakteristik endapan
laut. Struktur sedimen bioturbasi bermacam – macam sesuai dengan ukuran sedimen
dan kecepatan sedimennya. Struktur deformasi sedimen dapat dijumpai pada
lingkungan ini, sedangkan struktur sedimen akibat aktivitas gelombang jarang
dijumpai Prodelta ini kadang – kadang sulit dibedakan dengan endapan paparan
(shelf), tetapi pada prodelta ini sedimennya lebih tipis dan memperlihatkan pengaruh
proses endapan laut yang tegas (Allen, 1998).
Gambar 4.3.1. Morfologi lingkungan pengendapan pada delta (Allen, 1998)
29
Gambar 4.3.2 Model lingkungan pengendapan delta Mahakam (Allen, 1998)
Gambar 4.3.3. Pembagian lingkungan pada delta dengan ciri khas endapannya
(Allen et.al, 1998)
30
IV.4. Geometri Lapisan Batubara
Lapisan batubara umumnya dicirikan mempunyai koefisien variasi rendah
dengan geometri dan distribusi kadar sederhana, unsur-unsur utamanya mudah
dievaluasi, sedangkan unsur-unsur minor sulit dievaluasi. Secara umum geometri
lapisan batubara memang lebih sederhana bila dibandingkan dengan endapan mineral
yang lain (Spero Carras, 1984 dalam B. Kuncoro 2000). Meskipun demikian,
kenyataan di lapangan, selain ditemukan lapisan yang melampar luas dengan
ketebalan menerus dan dalam urutan yang teratur, juga dijumpai lapisan batubara
yang tersebar tidak teratur, tidak menerus, menebal, menipis, terpisah dan
melengkung dengan geometri yang bervariasi. Maka geometri menjadi perlu
dipelajari dan dipahami secara baik karena merupakan salah satu aspek penting di
dalam usaha mengembangkan industri pertambangan batubara. Adapun parameter
geometri lapisan batubara harus dikaitkan dengan kondisi penambangannya.
Pembagian parameter geometri lapisan batubara (Jeremic, 1985 dalam B. Kuncoro
2000) didasarkan pada hubungannya dengan terdapatnya lapisan batubara ditambang
dan kestabilan lapisannya meliputi :
1. Ketebalan
Ketebalan lapisan batubara adalah unsur penting yang langsung berhubungan
dengan perhitungan cadangan, perencanaan produksi, sistem penambangan dan umur
tambang. Oleh karena itu perlu diketahui faktor pengendali terjadinya kecenderungan
arah perubahan ketebalan, penipisan, pembajian, splitting dan kapan terjadinya.
Apakah terjadi selama proses pengendapan, antara lain akibat perubahan kecepatan
akumulasi batubara, perbedaan morfologi dasar cekungan, hadirnya channel, sesar,
dan proses karst atau terjadi setelah pengendapan, antara lain karena sesar atau erosi
permukaan. Pengertian tebal lapisan batubara tersebut adalah termasuk parting (gross
coal thickness), tebal lapisan batubara tidak temasuk parting (net coal thickness), dan
tebal lapisan batubara yang akan ditambang (mineable thickness).
2. Kemiringan
Besarnya kemiringan lapisan batubara berpengaruh terhadap perhitungan
cadangan ekonomis, dan sistem penambangan. Besarnya kemiringan harus
31
berdasarkan hasil pengukuran dengan akurasi tinggi. Dianjurkan pengukuran
kedudukan lapisan batubara menggunakan kompas dengan metode dip direction
sekaligus harus mempertimbangkan kedudukan lapisan batuan yang mengapitnya
(interburden).
3. Pola sebaran lapisan batubara
Pola sebaran lapisan batubara akan berpengaruh pada penentuan batas
perhitungan cadangan dan pembagian blok penambangan. Oleh karena itu, faktor
pengendalinya harus diketahui, yaitu apakah dikendalikan oleh struktur lipatan
(antiklin, sinklin, menunjam), homoklin, struktur sesar dengan pola tertentu atau
dengan pensesaran yang kuat.
4. Kemenerusan lapisan batubara
Selain jarak kemenerusan, maka faktor pengendalinya juga perlu diketahui,
yaitu apakah kemenerusannya dibatasi oleh proses pengendapan, split, sesar, intrusi
atau erosi. Misal pada split, kemenerusan lapisan batubara dapat terbelah oleh bentuk
membaji dari lapisan sedimen bukan batubara. Berdasarkan penyebabnya dapat
karena proses sedimentasi (autosedimentational splitt) atau tektonik yang ditujukan
oleh perbedaan penurunan dasar cekungan yang mencolok akibat sesar ( Werbroke,
1981 dalam Diessel, 1992). Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang split akan
sangat membantu pada :
a. Kegiatan eksplorasi untuk menentukan sebaran lapisan batubara dan
penentuan perhitungan cadangan.
b. Kegiatan penambangan hadirnya split dengan kemiringan sekitar 450
yang umumnya disertai dengan perubahan kekompakkan batuan,
maka akan menimbulkan masalah dalam kegatan tambang terbuka,
kestabilan lereng, dan kestabilan atap pada operasi penambangan
bawah tanah.
5. Keteraturan lapisan batubara
Keteraturan lapisan batubara ditentukan oleh pola kedudukan lapisan
batubara (jurus dan kemiringan) artinya apakah pola lapisan batubara dipermukaan
32
menunjukkan pola teratur (lurus, melengkung/meliuk pada elevasi yang hampir
sama) atau membentuk pola yang tidak teratur.
6. Bentuk lapisan batubara
Merupakan perbandingan antara tebal lapisan batubara dan kemenerusannya,
apakah melembar, membaji, melensa atau bongkah. Bentuk melembar merupakan
bentuk yang umum dijumpai, oleh karena itu selain bentuk melembar, maka perlu
dijelaskan faktor-faktor pengendalinya.
7. Roof dan Floor
Kondisi roof dan floor, meliputi jenis batuannya, kekerasan, jenis kontak,
kandungan karbonnya, bahkan sampai tingkat kerekatannya dalam kondisi kering
maupun basah. Kontak batubara dengan roof merupakan fungsi dari proses
pengendapannya.pada kontak yang tegas menunjukan proses yang tiba-tiba,
sebaliknya pada proses yang berlangsung lambat diperlihatkan oleh kontak yang
berangsur kandungan karbonnya. Roof banyak mengandung fosil, sehingga baik
untuk korelasi.
Litologi pada floor lebih bervariasi, seperti serpih, batulempung, batalanau,
batupasir, batugamping, atau soil yang umumnya masif. Bila berupa seatearth
umumnya mengandung akar tumbuhan, berwarna abu-abu cerah sampai coklat,
plastis, merupakan tanah purba tempat tumbuhan hidup, tidak mengandung alkali,
kandungan kalium dan besi rendah. Terjadi karena proses perlindihan oleh air yang
jenuh asam humik dari pembusukan tanaman.
8. Cleat
Cleat adalah kekar di dalam lapisan batubara, khususnya pada batubara
bituminous yang ditunjukkan oleh serangkaian kekar yang sejajar, umumnya
mempunyai orientasi yang berbeda dengan kedudukan lapisan batubara. Adanya
cleat dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: mekanisme pengendapan,
petrografi batubara, derajat batubara, tektonik (struktur geologi), dan aktivitas
penambangan.
33
Berdasarkan genesanya dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :
a. Endogenous cleat, dibentuk oleh adanya gaya internal akibat pengeringan
atau penyusustan material organik. Umunya tagak lurus bidang perlapisan
sehingga bidang kekar cenderung membagi lapisan batubara menjadi
fragmen-fragmen tipis yang tabular.
b. Exogenic cleat, dibentuk oleh gaya ekternal yang berhubungan dengan
kejadian tektonik. Mekanismenya tergantung dari karakteristik lapisan
pembawa batubara. Cleat ini terorientasi pada arah tegasan utama dan terdiri
dari dua pasang kekar yang saling memebentuk sudut.
c. Induced cleat, bersifat lokal akibat proses penambangan dengan adanya
perpindahan beban kedalam struktur tambang. Frekuensi induced cleat
tergantung pada tata letak tambang dan macam teknologi penambangan yang
digunakan.
besarnya pengaruh cleat menjadi penting untuk dipelajari dan diketahui
karena kehadiran dan orientasi cleat antara lain akan mempengaruhi pemilihan tata
letak tambang, arah penambangan, penerapan teknologi penambangan, proses
pengolahan batubara, penumpukan batubara, dan bahkan pemasaran batubara .
Oleh karena itu, perekaman data cleat tidak hanya terbatas pada kedudukan
dan kisaran jarak antar cleat, tetapi perlu dilengkapi dengan merekam jenis, pengisi,
pengendali terbentuknya.
9. Pelapukan
Tingkat pelapukan penting karena berhubungan dengan dimensi lapisan
batubara, kualitas, perhitungan cadangan dan penambangannya. Oleh karena itu
karakteristik pelapukan dan batas pelapukan harus ditentukan.
VI.5. Proses Pembentukan Gas Methane pada Batubara
Gas methane dalam batubara terbentuk akibat proses pembatubaraan
(Gambar4.4). Proses ini diawali dengan proses diagenesa gambut disebut juga
dengan tahap biokimia yang melibatkan perubahan kimia dan mikroba dimana pada
proses ini dimulai dengan dari proses pembentukan gambut yang merupakan hasil
34
dari aktivitas mikroba dan perubahan kimia. Kemudian dilanjutkan dengan tahap
pembatubaraan (coalification) tahap ini melibatkan perubahan kimia dan fisika serta
mengakibatkan perubahan batubara dari lignit sampai dengan antrasit. Tingkat
kematangan batubara ini Berhubungan dengan temperatur dan lamanya pemanasan
yang kemudian dengan semakin bertambahnya temperatur dan seiring dengan
bertambahnya waktu maka akan menyebabkan bertambahnya tekanan. Gas dalam
batubara dapat tebentuk secara biogenik maupun thermogenik.
Gambar 4.5. Proses Pembatubaraan (dalam Coalbed methane characteristics of the Gates
Formation coals, northestern British Columbia: effect of maceral composition, menurut
Lamberson, M.N. and Bustin, R.M., 1993)
1. Biogenik Gas
Biogenik gas terutama dalam bentuk gas methane CH4 dan CO2. Gas – gas ini
merupakan hasil dari penguraian bahan organik yang disebabkan oleh
mikroorganisme. Biogenik gas dapat terjadi dalam dua tahap, yaitu tahap awal dan
tahap akhir dari proses pembatubaraan.
• Tahap awal pembentukan gas biogenik : pada tahap ini gas terbentuk akibat
adanya aktivitas organisme pada awal proses pembatubaraan, dari
terbentuknya lignit sampai dengan subbituminous (Ro < 0.5 %).
35
Pembentukan gas ini diikuti dengan proses pengendapan yang sangat cepat,
karena jika tidak ada pengendapan yang cepat maka gas yang terbentuk tidak
akan tersimpan dalam batubara dan gas tersebut akan menguap ke atmosfer.
• Tahap akhir pembentukan gas biogenik : pada tahap ini gas terbentuk karena
adanya aktivitas mikroorganisme pada saat setalah lapisan batubaranya
sendiri terbentuk. Lapisan batubara yang terbentuk itu umumnya merupakan
aquifer, aktivitas mikroorganisme dalam aquifer tersebut dapat menghasilkan
gas methane. Proses ini dapat terjadi pada batubara dari semua rank batubara.
2. Thermogenik Gas
Thermogenik gas merupakan gas yang terbentuk pada tahap yang lebih tinggi
dari proses pembatubaraan. Gas ini terbentuk biasanya pada batubara yang telah
mencapai kualitas high volatile bituminous sampai dengan antasit. Proses
bituminisasi akan menghasilkan batubara yang kaya dengan kandungan karbon
dengan melepaskan kandungan utama volatile matter seperti methane, CO2 dan air.
VI.6. Maseral Pada Batubara
Maseral pada batubara analog dengan mineral pada batuan. Maseral
merupakan bagian terkecil dari batubara yang bisa teramati dengan mikroskop.
Maseral dikelompokan berdasarkan tumbuhan atau bagian tumbuhan menjadi tiga
grup (Gambar 4.6), yaitu :
1. Vitrinite
Vitrinite adalah maseral yang paling dominan dalam batubara. Maceral ini
berasal dari batang pohon, cabang, atau dahan, tangkai, daun, dan akar tumbuhan
pembentuk batubara. Nilai reflectance dari Vitrinite dijadikan penentu peringkat
batubara, dan sering dikorelasikan dengan nilai volatile matter seperti yang
terdapat pada ASTM standard.
2. Liptinite (Exinite)
Seperti namanya, Liptinite berasal dari spora, resin, alga, cutikula (yang terdapat
pada permukaan daun) lilin/parafin, lemak dan minyak. Suberinite, tidak
tercantum diatas, hanya terdapat pada batubara tersier. Maseral ini berasal dari
substansi semacam gabus yang terdapat pada kulit kayu, dan pada permukaan
36
akar, batang dan buah - buahan. Fungsi dari maseral ini sebenarnya untuk
mencegah pengeringan pada tanaman.
3. Inertinite
Material pembentuk inertinite sebenarnya sama dengan pembentuk Vitrinite.
Yang membedakannya adalah historikal pembentukannya yang disebut
fusination. Charring atau oksidasi pada saat proses pembentukan batubara
berlangsung merupakan proses yang membedakan substansi Vitrinite dan
Inertinite. Inertinite ini biasanya memiliki kadar carbon yang tinggi, hydrogen
yang rendah serta derajat aromatisisty yang tinggi.
Gambar 4.6. Klasifikasi Maseral
(dalam Part II Coal, Reservoir Issue menurut Crain.E. R. (Ross),P.Eng, 2010,)
IV.7. Data Batuan Inti (Core)
Batuan inti merupakan data bawah permukaan yang sangat penting sekaligus
merupakan satu-satunya data yang secara langsung memperlihatkan bukti nyata
kondisi bawah permukaan dan kondisi batuan itu sendiri. Pada coalbed methane data
core atau data inti batuan lebih lengkap lagi, yaitu dengan melakukan analisis
proximate, ultimate, dan total gas content.
VI.7.1. Analisis Proximate
Analisis proximate batubara adalah metode laboratorium yang sederhana
untuk menentukan komponen yang ada pada batubara, yang diperoleh pada saat
37
sampel batubara dipanaskan (pyrolisis) dibawah kondisi tertentu. Sampel batubara
diekstraksi dari sampel core kemudian ditempatkan pada canister untuk menjaga gas
dalam batubara tidak berkurang. Analisis ini menggunakan metode standar
berdasarkan ASTM D12, analisis proximate dikelompokkan menjadi :
• Ash
• Fixed carbon
• Volatile matter
• Moisture
Analisis ini berdasarkan standar ASTM D3172. Masing – masing pengukuran
ke empat parameter tersebut sangat penting dalam proses CBM.
Kandungan Ash pada batubara merupakan material yang tidak mudah
terbakar. Ash mewakili bulk mineral matter setelah karbon, oksigen, belerang dan
air (termasuk air yang ada didalam batulempung) yang telah dikeluarkan selama
proses pembakaran. Analisis ini cukup sederhana, dengan batubara secara
menyeluruh bakaran dan material Ash dinyatakan sebagai persentase yang berat.
Kandungan fixed carbon pada batubara merupakan kandungan batubara yang
tersisa setelah material volatile dihilangkan. Fixed carbon berbeda dengan
kandungan ultimate carbon dalam batubara karena beberapa carbon dalam
hidrocarbon akan hilang dengan volatile.
Kandungan moisture memiliki efek pada methane adsorption capacity.
Kandungan moisture ditentukan (ASTM D-3173) dengan cara memanaskan sampel
batubara yang berukuran kecil selama 1 jam pada vacuum atau pada atmosphere
nitrogen. Berat yang hilang pada sampel dinyatakan dalam percent yang kemudian
akan dilaporkan sebagai kandungan moisture. Analisis proximate biasanya
dilaporkan dalam bentuk percent ( % ) sebagai :
As received (ARB) = semua parameter (moisture, volatile matter, fixed
carbon, ash)
Ash free (AF) = tanpa ash
Dry = tanpa moisture
Dry, ash-free (DAF) = tanpa ash dan moisture
38
IV.7.2. Analisis Ultimate
Analisis Ultimate mencakup penentuan persen berat dari carbon, sulfur,
nitrogen, oksigen dan hidrogen. Pengukuran atau penentuan carbon termasuk cabon
organik yang merupakan bagian dari batubara. Pengukuran atau penentuan hidrogen
termasuk hidrogen yang hadir sebagai material organik maupun hidrogen yang
berasosiasi dengan air yang ada didalam batubara. Tidak adanya bukti yang
bertentangan, nitogen diasumsikan hadir pada organik matrix pada batubara.
Sebaliknya sulfur hadir dalam tiga bentuk dalam batubara :
1. Sulfur sebagai komponen organik
2. Anorganik Sulfides, umumnya kebanyakan hadir sebagai iron sulfides pyrite
dan marcasite (FeS2)
3. Anorganik sulfates, (seperti Na2SO4, CaSO4).
Nilai dari sulfur dapat dihasilkan dari analisis ultimate, tergantung pada
keadaan batubara dan beberapa metode prior untuk pembersihan batubara, anorganik
sulfur dan organik sulfur. Metode standar untuk analisis ultimate dari batubara
(ASTM D-3176) termasuk penentuan atau pengukuran elemen carbon, hidrogen,
sulfur dan nitrogen.
IV.7.3. Analisis Total Gas Content
Kandungan gas dalam batubara adalah parameter yang paling penting
mengetahui seberapa besar kandungan gas yang ada pada reservoir. Pengukuran
kandungan gas pada batubara dapat dilakukan di lapangan dan di laboratorium.
1. Pengukuran kandungan gas dalam batubara yang dilakukan di laboratorium
Pengukuran ini dibagi menjadi dua metode, yaitu :
• Metode pertama adalah berdasarkan desorpsi, perlahan alami gas dari
batubara. Pada metode ini, sampel batubara, dimasukkan dalam tabung
dan gas yang berasal dari batubara kemudian dikumpulkan dalam sebuah
gelas ukur terbalik dan kemudian akan menggalami perpindahan yang
dengan bantuan air ke dalam silinder.
• Metode kedua tergantung pada seberapa halus ukuran butir batubara, pada
metode ini batubara dihancurkan terlebih dahulu, hal tersebut dilakukan
39
dengan tujuan untuk mempercepat laju desorpsi gas. Metode ini
digunakan untuk mengetahui kandungan gas pada suatu lapisan batubara
(seam batubara), Metode pengukuran ini dilakukan di dalam ruangan
dengan membutuhkan waktu selam 2 hingga 3 jam.
2. Pengukuran kandungan gas dan kompsisisi gas dilapangan :
Pengukuran ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran gas
pada saat batubara dibawa ke laboratorium dan pengukuran ini juga
dilakukan untuk mengetahui dengan cepat kandungan gas pada batubara
tersebut. Sehingga untuk melakukan pengukuran ini dibutuhkan
menggunakan laboratorium mobile CBM yang merupakan kendaraan yang
dilengkapi dengan coal gas laboratory instruments. Laboratorium mobile
mampu untuk mengukur kandungan gas dan komposisi gas. Dengan
kendaraan ini, laboratorium dapat berada di lokasi pengeboran, sehingga
dapat menggurangi waktu untuk, mengirim tabung batubara ke laboratorium
dan mengurangi resiko adanya kebocoran gas selama transportasi.
IV.8. Data Log Sumur (Well Log)
Log merupakan suatu grafik kedalaman (bisa juga waktu) dari suatu data set
yang menunjukkan parameter yang diukur secara berkesinambungan di dalam sebuah
sumur (Harsono, 1997). Adapun parameter-parameter yang bisa diukur adalah sifat
kelistrikan (spontaneous potensial), tahanan jenis batuan, daya hantar listrik, sifat
keradioaktifan dan sifat meneruskan gelombang suara. Metode perekamannya
dengan menggunakan cara menurunkan suatu sonde atau sensor ke dasar lubang
pemboran. Beberapa jenis log yang digunakan dalam eksplorasi CBM diantaranya
adalah: (Gambar 4.7.)
40
Gambar 4.8. Visualisasi Batubara pada Log Sumur
a. Log Gamma Ray ( GR )
Prinsip log GR adalah perekaman radioaktivitas alami bumi. Radioaktivitas
GR berasal dari 3 unsur radioaktif yang ada dalam batuan yaitu Uranium – U,
Thorium – Th, dan Potasium – K, yang secara continue memancarkan GR dalam
bentuk pulsa – pulsa energi radiasi tinggi. Sinar Gamma ini mampu menembus
batuan dan dideteksi oleh sensor sinar gamma yang umumnya berupa detektor
sintilasi. Setiap GR yang terdeteksi akan menimbulkan pulsa listrik pada
detektor. Parameter yang direkam adalah jumlah dari pulsa yang tercatat per
satuan waktu (sering disebut cacah GR).
41
Batubara biasanya mempunyai respon natural gamma ray yang rendah
karena batubara murni mengandung unsur – unsur radioaktif alami yang rendah.
Tetapi kadang – kadang, pembacaan gamma ray lebih tinggi pada batubara
karena batubara teresebut mengandung mineral lempung yang kaya akan unsur-
unsur radioaktif alami. Peningkatan proses resolusi vertikal pada pengukuran
natural gamma ray dapat direkombenasikan dalam praktek aplikasi pada CBM.
Proses matematik ini mengurangi resolusi vertikal pada pengukuran, sharpening
the bed boundary membantu menyelidiki batubara secara teliti dan akhirnya akan
mendapatkan hasil yang lebih akurat dalam pengukuran ketebalan batubara.
b. Log Spontaneous Potensial (SP)
Kurva Log SP adalah rekaman perbedaan potensial antara elektroda yang
bergerak didalam lubang bor dengan elektroda dipermukaan yang disebabkan oleh
adanya 3 fenomena, yaitu : perbedaan salinitas antara fluida yang ada pada lubang
bor dan fluida yang ada pada reservoar, streaming potential, dan electrochemical
invasion. Pada batubara defleksi Spontaneous potential (SP) menunjukkan
permeabilitas pada batubara. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kombinasi
dari perbedaan salinitas dan streaming potential effects.
c. Log Resistivity
Alat pengukur resistivitas dibagi menjadi 2, yaitu : induction-based tool dan
lateralog. Alat pengukuran resistivitas yang sering digunakan dalam aplikasi CBM
adalah Induction-based tool. Umumnya batubara memiliki pengukuran resistivitas
yang tinggi pada batubara yang murni. Sedangkan pada batubara yang telah
terkontaminasi oleh mineral – mineral atau pengotor seperti mineral lempung,
pyrites, volcanic dan fluida yang mengisi cleat maka resistivitas pada batubara
tersebut dapat berkurang. Alat pengukuran resistivitas lateralog digunakan untuk
mengidentifikasi batubara yang permeabel dan batubara non permeabel. Batubara
permeabel dicirikan adanya invasion profile sedangkan batubara yang tight
menunjukan resistivitas yang sangat tinggi dengan tidak ada invasi.
42
d. Log Density
Log density merupakan suatu tipe log porositas yang mengukur densitas
elektron suatu formasi. Prinsip pencatatan dari log density adalah suatu sumber
radioaktif yang dimasukkan kedalam lubang bor mengemisikan sinar gamma ke
dalam formasi. Pada formasi tersebut sinar akan bertabrakan dengan elektron dari
formasi. Pada setiap tabrakan sinar gamma akan berkurang energinya. Sinar
gamma yang terhamburkan dan mencapai detektor pada suatu jarak tertentu dari
sumber dihitung sebagai indikasi densitas formasi. Jumlah tabrakan merupakan
fungsi langsung dari jumlah elektron didalam suatu formasi. Karena itu log
densitas dapat mendeterminasi densitas elektron formasi dihubungkan dengan
densitas bulk sesungguhnya didalam gr/cc. Harga densitas matrik batuan,
porositas, dan densitas fluida pengisi formasi. Log density merupakan log yang
sangat baik digunakan untuk megidentifikasi batubara. Pada log ini batubara
memiliki harga density yang rendah karena batubara memiliki density matrix
yang rendah.
Kandungan komponen kuarsa, seperti kuarsa yang berbutir halus dapat
memberikan efek yang sangat besar dalam pembacaan log density. Hal tersebut
dapat menyebabkan porositas semu batubara akan menurun sedangkan density
batubara akan meningkat.
e. Log Neutron
Log neutron merupakan tipe log porositas yang mengukur konsentrasi ion
hidrogen dalam suatu formasi. Di dalam formasi bersih di mana porositas diisi
air atau minyak, log neutron mencatat porositas yang diisi cairan. Neutron energi
tinggi yang dihasilkan oleh suatu sumber kimia ditembakkan ke dalam formasi,
sebagai akibatnya neutron kehilangan energinya. Kehilangan energi maksimum
akan terjadi pada saat neutron bertabrakan dengan atom hidrogen karena kedua
materi tersebut mempunyai massa yang hampir sama. Karena itu kehilangan
energi maksimum merupakan fungsi dari konsentrasi hidrogen dalam formasi,
karena dalam formasi yang sarang hidrogen terkonsentrasi didalam pori-pori
43
yang terisi cairan, maka kehilangan energi akan dapat dihubungkan dengan
porositas formasi. Log neutron merupakan salah satu log yang baik dalam
mengidentifikasi batubara. Pada log ini batubara memiliki harga neutron tinggi
karena umumnya batubara banyak mengandung unsur Hidrogen. Tetapi,
kandungan komponen ash yang lain, seperti kuarsa yang berbutir halus, dapat
mengurangi porositas neutron pada batubara.
f. Log Sonik
Log sonik merupakan suatu log yang mengukur interval waktu lewat dari
suatu gelombang suara kompressional untuk melalui suatu feet formasi. Interval
waktu lewat dengan satuan mikrodetik per kaki merupakan kebalikan kecepatan
gelombang suara kompresional (satuan feet per detik). Harga log sonik
tergantung pada litologi dan porositas. Pada log ini batubara memiliki porositas
yang tinggi. Kandungan mineral lempung pada batubara tidak memiliki pengaruh
yang besar terhadap pembacaan porosity pada log ini. Hal tersebut karena
porositas pada mineral lempung murni memiliki kisaran yang sama dengan
porositas batubara. Tetapi, kandungan komponen ash yang lainnya, seperti
kuarsa yang berbutir halus dapat menyebabkan penurunan porosity pada
batubara.
IV.9. Korelasi
Korelasi merupakan langkah penentuan unit stratigrafi dan struktur yang
mempunyai persamaan waktu, umur dan posisi stratigrafi. Korelasi digunakan untuk
keperluan pembuatan penampang dan peta bawah permukaan untuk kemudian
dilakukan evaluasi formasi, penentuan zona produktif atau ada tidaknya perubahan
secara lateral dari masing-masing perlapisan. Dalam pelaksanaannya, korelasi
melibatkan aspek seni dan ilmu, yaitu memadukan persamaan pola dan prinsip
geologi, termasuk dalam proses dan lingkungan pengendapannya, pembacaan dan
analisis log, dasar teknik reservoar serta analisis kualitatif dan kuantitatif. Data yang
dipakai dalam korelasi umumnya adalah integrasi data core, data wireline log dan
data seismik.
44
Korelasi adalah suatu pekerjaan menghubungkan suatu titik pada suatu
penampang stratigrafi dengan titik lain dari penampang stratigrafi yang lain pula
dengan anggapan bahwa titik-titik tersebut terletak pada perlapisan yang sama.
Dalam sandi stratigrafi Indonesia (1996) disebutkan korelasi adalah penghubungan
titik-titik kesamaan waktu atau penghubungan satuan-satuan stratigrafi dengan
mempertimbangkan kesamaan waktu.
Tujuan Korelasi
• Mengetahui dan merekontruksi kondisi bawah permukaan (struktur dan
stratigrafi) serta mengetahui penyebaran lateral maupun vertikal dari zona
hidrokarbon (penentuan cadangan).
• Merekontruksi paleogeografi daerah telitian pada waktu geologi tertentu,
yaitu dengan membuat penampang stratigrafi.
• Menafsirkan kondisi geologi yang mempengaruhi pembentukan hidrokarbon,
migrasi dan akumulasinya didaerah telitian.
• Menyusun sejarah geologi daerah telitian.
Faktor-faktor yang menjadikan dasar korelasi :
• Tujuan pekerjaan korelasi
• Tingkat kompleksitas struktur geologi daerah telitian.
• Tingkat perkembangan dan penyebaran endapan secara lateral ditinjau dari
aspek litologis maupun paleontologis.
• Waktu yang tesedia.
• Jenis data dan tingkat kelengkapannya.
• Kemampuan dan pengalaman peneliti.
Konsep penting dalam korelasi :
a. Bidang pelapisan adalah unsur utama pembentuk satuan stratigrafi dan bentuk-
bentuk struktur sekaligus menentukan hubungan stratigrafi dan tektonik dari
masing-masing satuan dan bentuk-bentuk struktur tersebut.
45
b. Bidang perlapisan merupakan bidang kesamaan waktu.
c. Hukum superposisi.
Metode korelasi menurut Koesoemadinata (1971), yaitu :
a. Metode Organik
Metode korelasi organik merupakan pekerjaan menghubungkan satuan-
satuan stratigrafi berdasarkan kandungan fosil dalam batuan (biasanya
foraminifera planktonik). Yang biasa digunakan sebagai marker dalam korelasi
organik adalah asal munculnya suatu spesies dan punahnya spesies lain. Zona
puncak suatu spesies, fosil indek, kesamaan derajat evolusi dan lain-lain.
b. Metode Anorganik
Pada metode korelasi anorganik penghubungan satuan-satuan stratigrafi
tidak didasarkan pada kandungan organismenya (data organik).
Korelasi dari Log Mekanik
Sebagian besar pekerjaan korelasi pada industri minyak dan gas bumi
menggunakan data log mekanik. Tipe-tipe log yang biasa digunakan antara lain log
penafsir litologi (GR, SP) yang dikombinasikan dengan log resistivitas atau log
porositas (densitas, neutron dan sonik). Pemilihan tipe log untuk korelasi tergantung
pada kondisi geologi daerah yang bersangkutan. Kombinasi log SP dan resistivitas
biasa digunakan pada cekungan silisiklastik sementara, untuk cekungan karbonat
digunakan log GR kombinasi dengan log resistivity atau log GR kombinasi dengan
log neutron.
Prosedur korelasi
Langkah-langkah korelasi dengan log mekanik adalah sebagai berikut :
a. Menentukan horison korelasi dengan cara membandingkan log mekanik dari
suatu sumur tertentu terhadap sumur yang lain dan mencari bentuk-bentuk atau
pola-pola log yang sama atau hampir sama.
46
b. Setelah bentuk atau pola log yang relatif sama didapatkan dan telah dinyakini
pula bahwa bentuk dan pola tersebut mewakili perlapisan yang sama,
selanjutnya dilakukan pekerjaan menghubungkan bentuk-bentuk kurva yang
sama atau hampir sama dari bagian atas kearah bawah secara kontinyu. Korelasi
secara top down dihentikan jika korelasi tidak bisa dilakukan lagi, kemudian
korelasi dilakukan secara bottom up. Adanya zona-zona yang tidak bisa
dikorelasikan dapat ditafsirkan kena pengaruh struktur (patahan,
ketidakselarasan) atau stratigrafi (pembajian, channel fill, pemancungan,
perubahan fasies).
c. Setelah korelasi selesai dilakukan akan didapatkan penampang melintang, baik
penampang struktur maupun penampang stratigrafi. Dalam pembuatan
penampang struktur datum diletakkan pada kondisi seperti pada keadaan saat ini
(biasanya sea level sebagai datum).
IV.10. Elektrofasies
Elektrofasies dianalisis dari pola kurva log gamma ray (GR). Menurut Selley
(1978) dalam Walker (1992), log gamma ray mencerminkan variasi dalam satu
suksesi ukuran besar butir. Suatu suksesi ukuran besar butir tersebut menunjukkan
perubahan energi pengendapan (Levy, 1991). Tiap-tiap lingkungan pengendapan
menghasilkan pola energi pengendapan yang berbeda. Menunjukkan lima pola
bentuk dasar dari kurva log GR, sebagai respons terhadap proses pengendapan.
Berikut ini adalah penjelasan mengenai bentuk dasar kurva log: (Gambar 4.8)
a. Cylindrical
Bentuk silinder pada log GR atau log SP dapat menunjukkan sedimen tebal
dan homogen yang dibatasi oleh pengisian channel (channel-fills) dengan
kontak yang tajam. Cylindrical merupakan bentuk dasar yang mewakili
homogenitas dan ideal sifatnya. Bentuk cylindrical diasosiasikan dengan
endapan sedimen braided channel, estuarine atau sub-marine channel fill,
anastomosed channel, eolian dune, tidal sand.
47
b. Irregular
Bentuk ini merupakan dasar untuk mewakili heterogenitas batuan reservoar.
Bentuk irregular diasosiasikan dengan regressi alluvial plain, floodplain,
tidal sand, shelf atau back barriers. Umumnya mengidentifikasikan lapisan
tipis silang siur (thin interbedaed). Unsur endapan tipis mungkin berupa
creavasse splay, overbanks regressi dalam laguna serta turbidit.
c. Bell Shape
Profil berbentuk bell menunjukkan penghalusan ke arah atas, kemungkinan
akibat pengisian channel (channel fills). Pengamatan membuktikan bahwa
range besar butir pada setiap level cenderung sama, namun jumlahnya
memperlihatkan gradasi menuju berbutir halus (dalam arti lempung yang
bersifat radioaktif makin banyak ke atas). Bentuk bell dihasilkan oleh
endapan point bars, tidal deposits, transgresive shelfsands (Dominated tidal),
sub marine channel dan endapan turbidit.
d. Funnel shape
Profil berbentuk corong (funnel) menunjukkan pengkasaran regresi atas yang
merupakan bentuk kebalikan dari bentuk bell. Bentuk funnel kemungkinan
dihasilkan regresi progradasi seperti sub marine fan lobes, regressive shallow
marine bar, barrier islands atau karbonat terumbu depan yang berprogradasi
di atas mudstone, delta front (distributary mounth bar), creavase splay, beach
dan barrier beach (barrier island), strandplain, shoreface, prograding
(shallow marine) shelf sands dan submarine fan lobes.
e. Symmetrical-Asymetrical Shape
Bentuk symmetrical merupakan kombinasi antara bentuk bell-funnel.
Kombinasi coarsening-finning upward ini dapat dihasilkan oleh proses
bioturbasi. Selain tatanan secara geologi yang merupakan ciri dari shelf sand
bodies, submarine fans dan sandy offshore bars. Bentuk asymmetrical
merupakan ketidakselarasan secara proporsional dari kombinasi bell-funnel
pada lingkungaan pengendapan yang sama.
49
BAB V
PENYAJIAN DATA
Penelitian fasies batubara dan karakteristik petrofisik batubara Lapangan “X”,
Formasi Balikpapan, seam CBM2, Cekungan Kutai menggunakan data inti batuan
dan data log sumur. Data inti batuan dan data log sumur mempergunakan 8 buah
sumur. Data tersebut dapat diperinci sebagai berikut :
V.1. Data Inti Batuan
Dalam penelitian ini mempergunakan data inti batuan dari 8 buah sumur
dengan rincian data yang didapatkan pada Tabel 5.1. Data tersebut dapat digunakan
untuk mengidentifikasi faises dan karakteristik petrofisik dari batubara, lapangan
“X”, Formasi Balikpapan, seam CBM2, Cekungan Kutai.
Tabel 5.1. Data Inti Batuan yang tersedia pada sumur
Sumur Analisis Proximate
Analisis Ultimate
Calorific Value
(Kcal/kg)
Helium Pycnometric
Density (g/cc)
Bulk Density (g/cc)
Mean Vitrinite
Reflectance (% Ro)
Analisis Maceral
Deskripsi Inti
Batuan (Core)
X-1
X-2 X-3 X-4 X-5 X-6 X-7 X-8
50
V. 2. Data Log Sumur
Dalam penelitian mempergunakan data log sumur dari 8 buah sumur dengan
rincian pada Tabel 5.2 dan contoh tampilan log dapat X 1 ( Gambar 5.1 ). Data log
sumur ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi fasie dan karakteristik petrofisik
dari batubara lapangan “X”, Formasi Balikpapan, seam CBM2, Cekungan Kutai.
Tabel 5.1. Data Log yang tersedia pada sumur.
Sumur GR Resistivity
RHOB NPHI DT AO10 AO20 AO30 AO60 AO90
X-1
X-2 X-3 X-4 X-5 X-6 X-7 X-8
52
BAB VI
HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN
Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, analisis
analisis lingkungan pengendapan, analisis geometri seam, analisis petrofisik dan
analisis penyebaran parameter petrofisik berdasarkan berdasarkan data core dan data
wireline log dari delapan sumur. Penelitian ini difokuskan pada formasi lapisan
batubara seam CBM 2 yang berperan sebagai reservoar.
VI.1 Analisis Lingkungan Pengendapan
Analisis lingkungan pengendapan batubara seam CBM2 menurut model
Horne, 1987 adalah lingkungan pengendapan Transitional Lower Delta Plain
(Gambar 6.1.1) hal ini ditunjukan juga dengan keberadaan batubara seam CBM2
yang tebalnya dapat mencapai lebih dari 10 m di daerah telitian dan juga dapat
ditunjukan dengan adanya pola log sumur yang sesuai dengan pola yang ada pada
lingkungan pengendapan Transitional Lower Delta Plain menurut Horne, 1987
(Gambar). Disamping itu seam CBM ini memiliki kandungan sulfur agak rendah dan
dibeberapa daerah terdapat spliting.
Gambar 6.1.1 Lingkungan Pengendapan Seam CBM 2 menurut Horne, 1978
Penulis melakukan analisis lingkungan pengendapan meurut model Horne,
1978 dengan cara mengidentifikasi pola-pola dari log sumur pada seam CBM 2. Pada
53
log sumur tersebut penulis mengidentifikasikan bahwa seam CBM 2 termasuk dalam
lingkungan pengendapan transitional lower delta plain. Karena pada log sumur
menunjukkan pola menghalus keatas yang menunjukkan adanya endapan channel,
swamp, interdistributary bay, dan creavasse splay (Gambar 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4).
Gambar 6.1.2. Identifikasi pola log sumur X201 berdasarkan model Horne 1978
Gambar 6.1.3. Identifikasi pola log sumur X71 berdasarkan model Horne 1978
54
Gambar 6.1.4. Identifikasi pola log sumur X60 dengan menggunakan model Horne 1978
Analisis lingkungan pengendapan batubara seam CBM 2 menurut
Allen,1998 ini dilakukan dengan membuat korelasi stratigrafi. Pada korelasi
stratigrafi penulis menggunakan datum maximum flooding surface. Penulis memilih
datum tersebut karena maximum flooding surface adalah marine flooding surface
yang terbentuk pada waktu transgresi maksimum. Dimana maximum flooding
surface dapat menjadi batas antara proses pengendapan yang satu dengan yang
lainnya. Dari analisis lingkungan pengendapan menurut Allen, 1998 didapatkan
hasil seam CBM2 termasuk dalam lingkungan pengendapan Delta plain (Gambar
6.1.6.). Hal ini ditunjukkan pada korelasi stratigrafi (Gambar 6.1.7.) dimana adanya
endapan distributary channel yang berasosiasi dengan seam CBM2.
55
Gambar 6.1.6. Model Lingkungan Pengendapan Menurut Allen (1998)
Gambar 6.1.7. Korelasi Stratigrafi
Dari korelasi startigrafi tersebut maka penulis dapat melihat analisis
elektrofasies dari log gamma ray. analisis tersebut dapat digunakan dalam
mengidentifikasi lingkungan pengendapan seam CBM 2. Beberapa contoh
identifikasi analisis elektrofasies sebagai berikut : (Gambar 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10).
Pada analisis elektrofasies ini didapatkan terdapat pola log berupa Cylindricall shape
yang cenderung menghalus keatas (finning upward) yang dapat diidentifikasikan
sebagai fasies distributary channel, kemudian terdapat juga pola log berupa bell
shape yang cenderung menghalus ke arah atas (finning upward) yang
diidentifikasikan sebagai faseis interdistibutary channel dan swamp. Berdasarkan
analisis elektrofasies maka didapatkan bahwa seam CBM 2 memiliki lingkungan
pengendapan delta plain.
56
Gambar 6.1.8. Analisis Elektrofasies Pada Sumur X201
Gambar 6.1.9 Analisis Elektrofasies Pada Sumur X71
57
Gambar 6.1.10 Analisis elektrofasies pada sumur X60
Dari analisis lingkungan pengendapan serta berdasarkan korelasi stratigrafi,
penulis mencoba membuat peta fasies batubara seam CBM 2 (Gambar 6.1.11)
dalam bentuk tiga dimensi. Pada peta fasies batubara ini penulis, membagi lima
lapisan, yang terdiri dari delta plain dan delta front. Pada peta fasies ini lapisan
batubara seam CBM 2 berada pada lapisan paling atas yang diendapakan pada
lingkungan delta plain.
58
Gambar 6.1.11. Peta fasies batubara seam CBM 2
VI.2. Analisis Geometri Batubara
Analisis geometri seam CBM 2 dilakukan dengan metode pembuatan peta
ketebalan batubara. Dari hasil pembuatan peta ketebalan dan peta kedalaman
batubara (Gambar 6.2.1, 6.2.2) dapat diketahui ketebalan batubara seam CBM 2
pada daerah telitian sekitar 5 – 35 ft. Selain itu penulis dapat mengidentifikasi arah
pengendapan seam CBM 2, yaitu Barat Laut – Tenggara hal tersebut dapat terlihat
dari arah garis konur pada peta ketabalan batubara. Disamping itu penulis dapat
mengidentifikasikan bahwa seam CBM 2 ini semakin menebal ke arah tenggara dan
menipis kearah barat laut hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh lingkungan
pengendapan. Berdasarkan hasil overlay (Gambar 6.2.3) dari peta ketebalan dan
peta kedalaman batubara dapat diketahui beberapa daerah prospek yaitu berada di
kedalaman sekitar 4000 hingga 4400 ft dengan ketebalan batubara mencapai 35 ft
atau 11.67 m.
62
VI.3. Analisis Petrofisik
Analisis petrofisik dapat dilakukan setelah terlebih dahulu melakukan
beberapa analisis data core yang telah didapatkan dari laboratorium berupa hasil
pengukuran dari beberapa analisis. Analisis tersebut mencakup analisis proximate,
analisis ultimate, analisis maceral dan analisis kandungan gas. Pada analisis
petrofisik ini menggunakan data yang dihasilkan dari analisis proximate, kemudian
dari data tersebut dilakukan analisis dengan membuat beberapa crossplot untuk
mendapat rumus yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan parameter
petrofisik dan pembuatan model penyebaran parameter petrofisik.
Dalam perhitungan petrofisik juga memerlukan nilai dari density ash dan
density batubara. Untuk mendapatkan nilai atau harga dari denisity ash dan density
batubara penulis membuat crossplot antara helium density dan % Ash
(Gambar.6.3.1). Penulis mengunakan helium density dan ash karena helium density
mempunyai hubungan yang baik dengan bahan anorganik seperti Ash.
Gambar.6.3.1 Crossplot antara Helium Density dengan %Ash
63
Dari crossplot diatas maka didapatkan :
Density batubara = 1.29
Density ash = 2.5
Sebelum penulis memilih parameter yang dapat digunakan untuk melakukan
perhitungan petrofisik. Terlebih dahulu penulis melakukan analisis dengan cara
membuat crossplot antara density dari data log dengan density dari data core berupa
bluk density (Gambar.6.3.2). Dari crossplot penulis mendapatkan hasil yang baik
yaitu density dari log dan density dari data core memiliki korelasi yang baik.
Sehingga penulis dapat menggunakan density dari data log (RHOB) dan density dari
data core untuk melakukan perhitungan petrofisik ke semua sumur yang ada.
Gambar.6.3.2. Crossplot antara density dari log dengan density dari core
64
Setelah mengetahui parameter yang dapat digunakan untuk melakukan
analisis dan perhitungan petrofisik, kemudian dilakukan analisis petrofisik pada salah
satu kompenen dari batubara, yaitu ash. Analisis ini dilakukan dengan membuat
crossplot antara % ash dengan RHOB ( Density dari Log ) (Gambar.6.1.3.) Dari
crossplot tersebut didapatkan rumus yang dapat digunakan untuk melakukan
perhitungan petrofisik dari komponen tersebut berupa % ash.
Gambar.6.3.3. Crossplot % Ash dan RHOB
Kemudian analisis ini dilanjutkan dengan melakukan analisis untuk
mendapatkan formula atau rumus yang dapat digunakan untuk menghitung
kandungan fixed carbon. Analisis ini dilakukan dengan membuat crossplot antara %
ash (ARB) dengan % fixed carbon (ARB) berdasarkan seam (Gambar.6.3.4). Dari
crossplot ini dapat diketahui bahwa crossplot pada semua seam relatif memiliki
kesamaan arah atau memiliki korelasi.
65
Gambar.6.3.4. Crossplot % Ash dan % Fixed Carbon
Kemudian analisis ini dilanjutkan dengan melakukan analisis untuk
mendapatkan formula atau rumus yang dapat digunakan untuk menghitung
kandungan moisture. Analisis ini dilakukan dengan membuat crossplot antara % ash
(ARB) dengan % moisture (ARB) berdasarkan seam (Gambar.6.3.5). Dari crossplot
tersebut dapat diketahui bahwa semua seam relatif memiliki kesaman arah dan
memiliki korelasi antara seam satu dengan seam yang lainnya.
Gambar.6.3.5. Crossplot antara % Ash dengan % Moisture
66
Terakhir dilakukan analisis untuk mendapatkan formula atau rumus yang
dapat digunakan untuk menghitung kandungan volatile matter. Analisis ini dilakukan
dengan membuat crossplot antar % ash (ARB) dengan % volatile matter (ARB)
berdasarkan seam (Gambar.6.3.6). Dari crossplot tersebut dapat diketahui bahwa
semua seam relatif memiliki kesaman arah dan memiliki korelasi antara seam satu
dengan seam yang lainnya. Dari crossplot ini juga didapatkan hasil bahwa semakin
tinggi kandungan volatile matter maka semakin juga rendah kandungan ash sehingga
dapat disimpulkan lebih lanjut dengan semakin banyak kandungan ash berarti
semakin sedikit juga kandungan gas yang ada ada pada batubara.
Gambar.6.3.6. Crossplot antara % Ash dengan % Volatile Matter
Dari semua crossplot tersebut dapat diketahui bahwa fixed carbon, moisture
dan volatile matter dari semua seam memiliki arah yang sama dan memiliki korelasi
antara seam satu dengan seam yang lainnya , sehingga untuk mendapatkan formula
atau rumus yang dapat digunakan untuk menghitung semua parameter tersebut.
Dapat dilakukan analisis dengan membuat satu crossplot antara % ash dengan semua
parameter (fixed carbon, moisture, dan volatile matter). (Gambar.6.3.7). Kemudian
dari hasil crossplot tersebut didapatkan formula untuk menghitung semua parameter
petrofisik yang kemudian dapat digunakan untuk membuat kalibrasi data log dan
67
data core, serta dapat digunakan dalam pembuatan model penyebaran parameter
petrofisik.
Gambar.6.3.7. Crossplot antara % Ash dengan % Semua Parameter ( Fixed Carbon, Moisture dan Volatile Matter)
Dari crossplot tersebut didapatkan beberapa formula yang dapat digunakan
untuk menghitung parameter – parameter petrofisik, sebagai berikut :
% Ash = (33.15 x RHOB) – 39.29
% Fixed Carbon = 44.73 – (0.547 x % Ash)
% Volatile Matter = 39.68 – (0.378 x % Ash)
% Moisture = 100 - % Ash - % Fixed Carbon - % Volatile Matter
Setelah penulis melakukan analisis dan mendapatkan formula yang dapat
digunakan untuk perhitungan parameter – parameter petrofisik. Kemudian penulis
melakukan analisis untuk mengetahui hubungan antara total gas content dengan
kandungan mean vitrinite reflectance dengan membuat crossplot (Gambar 6.3.8).
Dari crossplot tersebut penulis dapat mengetahui hubungan antara total gas content
68
dengan kandungan mean vitrinite reflectance, yaitu semakin tinggi kandungan mean
vitrinite reflectance maka semakin besar kandungan total gas dan berdasarkan
crossplot tersebut penulis mendapatkan formula yang dapat digunakan untuk
menghitung total gas content.
Gambar.6.3.8. Crossplot antara % Total Gas Content dengan % Mean Vitrinite Reflectance
VI.4. Kalibrasi Data Inti Batuan (Core) ke Data Log Sumur (Well Log)
Kalibrasi data inti batuan (core) dengan data log dapat dilakukan setelah
penulis melakukan analisis petrofisik. Karena dengan melakukan analisis petrofisik
penulis dapat mengetahui karakteristik petrofisik dari beberapa komponen penting
yang terkandung di dalam batubara dan dari hasil analisis petrofisik tersebut juga
penulis mendapatkan formula atau rumus yang dapat digunakan dalam melakukan
kalibrasi data inti batuan (core) dan data log. Kalibrasi ini sangat penting bagi
penulis untuk mengetahui hubungan dari data core dengan data log (Gambar.5.2.1).
Dari hasil kalibrasi yang dilakukan penulis didapatkan hasil yang baik. Sehingga
dapat diketahui hubungan antara data core dengan data log mempunyai korelasi.
Sehingga formula atau rumus yang didapatkan dari analisis petrofisik dapat
digunakan dalam perhitungan parameter petrofisik di sumur – sumur yang lainnya.
69
Gambar 6.4.1.Kalibrasi Data Inti Batuan (core) ke Data Log Sumur (Well Log)
VI.5. Analisis Penyebaran Parameter Petrofisik
Setelah dilakukan analisis kualitatif maupun kuantitatif yang menghasilkan
nilai dari parameter petrofisika, lalu diketahui ketebalan reservoar yang berpotensi
coalbed methane, selanjutnya dilakukan pembuatan peta. Pada penelitian ini
pembuatan peta dilakukan dengan menggunakan pendekatan geofisika yang
berisikan analisis variogram, sehingga menghasilkan peta simulasi yang
menggambarkan hubungan antar titik contoh pada jarak tertentu. Pemetaan ini
dilakukan pada Lapangan “X”, yang menjadi objek kajian penelitian. Peta Reservoar
dibuat terlebih dahulu, untuk mengetahui penyebaran batuan reservoar di daerah
kajian penelitian. Selanjutnya dibuat peta yang menunjukkan penyebaran properti
batuan seperti ash, fixed carbon, dan moisture, yang menggambarkan lapisan yang
berpotensi coalbed methane. Pembuatan peta properti batuan ini mengacu kepada
peta reservoar yang dibuat sebelumnya.
70
VI.5.1 Penyebaran Batubara dan Non Batubara
Peta ini menggambarkan penyebaran batubara yang ada pada daerah kajian
penelitian (Gambar 6.5.1.). Terlihat pada gambar, bahwa batubara yang ditunjukkan
oleh warna hitam, menyebar secara umum di bagian baratlaut menerus ke bagian
tengah hingga ke bagian tenggara sedangkan non batubara yang ditunjukkan oleh
warna kuning. Pada peta penyebaran ini juga dapat terlihat juga pola pengendapan
dari batubara tersebut.
Gambar.6.5.1.Peta penyebaran batubara dan non batubara
71
VI.5.2. Model Penyebaran Ash
Model ini menunjukkan penyebaran kandungan ash pada batubara pada zona
reservoar CBM 2 (Gambar 6.5.2.). Terlihat pada gambar pola penyebaran
kandungan ash mengikuti pola persebaran reservoar batubara. Setelah mendapatkan
model penyebaran kandungan ash, penulis membuat peta penyebaran kandungan ash
(Gambar 6.5.2.1) untuk mengetahui pola penyebaran kandungan ash pada seam
CBM 2. Sehingga dengan mengetahui pola sebaran kandungan ash tersebut dapat
diketahui beberapa daerah yang berpotensi sebagai reservoar untuk coalbed methane.
Gambar.6.5.2.Model Penyebaran Kandungan Ash
73
VI.5.3. Model Penyebaran Fixed Carbon
Model ini menunjukkan penyebaran kandungan fixed carbon pada batubara
pada zona reservoar CBM 2 (Gambar 6.5.3.). Terlihat pada gambar pola penyebaran
kandungan fixed carbon mengikuti pola persebaran reservoar batubara. Setelah
mendapatkan model penyebaran kandungan fixed carbon, penulis membuat peta
penyebaran kandungan fixed carbon (Gambar 6.5.3.1) untuk mengetahui pola
penyebaran kandungan fixed carbon pada seam CBM 2. Sehingga dengan
mengetahui pola sebaran kandungan fixed carbon tersebut dapat diketahui beberapa
daerah yang berpotensi sebagai reservoar untuk coalbed methane.
Gambar.6.5.2.Model Penyebaran Kandungan Fixed Carbon
75
VI.5.4. Model Penyebaran Kandungan Moisture
Model ini menunjukkan penyebaran kandungan moisture pada batubara pada
zona reservoar CBM 2 (Gambar 6.5.4.). Terlihat pada gambar pola penyebaran
kandungan moisture mengikuti pola persebaran reservoar batubara. Setelah
mendapatkan model penyebaran kandungan moisture, penulis membuat peta
penyebaran kandungan moisture (Gambar 6.5.4.1) untuk mengetahui pola
penyebaran kandungan moisture pada seam CBM 2. Sehingga dengan mengetahui
pola sebaran kandungan moisture tersebut dapat diketahui beberapa daerah yang
berpotensi sebagai reservoar untuk coalbed methane.
Gambar.6.5.4. Model Penyebaran Kandungan Moisture
77
VI.5.5. Overlay Peta Kedalaman, Peta Ketebalan dan Peta Penyebaran
Kandungan Moisture
Setelah mengetahui model dari penyebaran parameter batubara maka penulis
mencoba membuat overlay antara model penyebaran moisture, peta kedalaman dan
peta ketebalan batubara (Gambar.6.3.3.a). Dari hasil overlay tersebut didapatkan
beberapa daerah yang berpotensi sebagai daerah yang baik untuk eksplorasi coalbed
methane dan berpotensi sebagai daerah eksplorasi batubara sebagai bahan bakar yang
ekonomis adalah daerah yang memiliki kandungan moisture yang rendah, dimana
berdasarkan peta kedalaman dan peta ketebalan. Daerah ini memiliki ketebalan
lapisan batubara sebesar 20 ft hingga 35 ft atau sebesar 6.67 m hingga 11.67 m yang
berada pada kedalaman sekitar 4000 ft hingga 4400 ft atau sekitar 1.333 m hingga
1.466 m dengan kandungan moisture sebesar 1.3 %.
79
BAB VII
KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang dilakukan pada parameter batubara dengan
melakukan analisis pertofisik, analisis model penyebaran parameter petrofisik
batubara dan analisis lingkungan pengendapan, maka didapatkan hasil sebagai
berikut :
1. Lingkungan pengendapaan lapisan batubara seam CBM 2 berdasarkan Horne,
1978 adalah Transitional Lower Delta Plain dan Lingkungan pengendapan
lapisan batubara seam CBM 2 berdasarkan Allen, 1998 adalah Delta Plain.
2. Geometri seam CBM 2 dapat diketahui ketebalan batubara seam CBM 2 pada
daerah telitian sekitar 5 – 35 ft dan arah pengendapan seam CBM 2, yaitu
Barat Laut – Tenggara. Disamping seam CBM 2 menebal kearah tenggara
dan menipis kearah barat laut.
3. Berdasarkan analisis petrofisik didapatkan karakteristik petrofisik dari seam
CBM 2, nilai tertinggi dari kandungan ash sebesar 2.68 %, fixed carbon
sebesar 46.07 %, volatile matter sebesar 41.28 %, moisture sebesar 0.11 %,
mean vitrinite reflectance sebesar 0.45 %, total gas content sebesar 127.88
scft/ton dan kalori sebesar 6260 Kcal/kg. Dari hasil tersebut penulis dapat
diketahui bahwa seam CBM 2 memiliki kualitas yang baik berdasarkan
ASTM coal rank yaitu termasuk dalam batubara jenis bituminous high
volatile C, sehingga berpotensi sebagai reservoar coalbed methane dan
sebagai bahan bakar yang ekonomis.
4. Berdasarkan hasil overlay dari peta penyebaran kandungan moisture, peta
fasies batubara, peta kedalaman, peta ketebalan batubara dan peta geologi.
Didapatkan daerah yang berpotensi untuk eksplorasi batubara dan coalbed
methane pada seam CBM2. Daerah telitian ini memiliki struktur geologi
berupa perlipatan antiklin yang berarah utara timur laut – selatan barat daya,
diendapkan pada lingkungan pengendapan delta plain yang berdasarkan
80
analisis ultimate didapatkan kandungan sulfur yang rendah, yaitu sekitar 0.4
%, berada pada kedalaman sekitar 4000 hingga 4400 ft dengan ketebalan
batubara mencapai 35 ft atau 11.67 m dengan kandungan % moisture relatif
rendah, yaitu 1.3 %, Sehingga dapat disimpulakan daerah ini memiliki
potensi sebagai daerah eksplorasi coalbed methane dan batubara pada seam
CBM 2.
81
DAFTAR PUSTAKA
Allen,G.P, Chambers, J.L.C,1998, Sedimentation in the Modern and Miocene
Mahakam Delta, IPA.
Bhanja .A. K, 2007, Multi Log Techniques for Estimation of CBM Gas Content
Scores Over the Available Techniques Based on Single Log, A Case Study.
Kuncoro Prasongko, B, 1996, Perencanaan Eksplorasi Batubara, Program Pasca
Sarjana Institut Teknologi Bandung.
Lamberson, M.N. and Bustin, R.M., 1993: Coalbed methane characteristics of the
Gates Formation coals, northestern British Columbia: effect of maceral
composition. AAPG Bull,77; p2062-2076.
Rahmat. Basuki. Ediyanto,2008,Modul Kompetensi Geologi Level 3 (Bahan Galian
Batubara).
Crain.E. R. (Ross),P.Eng, 2010, Part II Coal, Reservoir Issue.
Holmes, M., 2001, Coalbed Methane Log Analysis, Digital Formation, 6000 East
Evans Avenue Suite 1-400 Denver, Colorado 80222-5415 USA.
Petrolog, Introduction to Coal Bed Methane Processing.
Rogers, R., Ramurthy, M., Rodvelt, G., and Mullen, M.. 2007, Coalbed Methane
Principles and Practices Second Edition, Halliburton.
Ryan, B., 2006, A Discussion on Moisture in Coal Implications for coalbed gas and
coal utilization, Summary of activities, BC Ministry of Energy, Mines and
Petroleum Resources, pages 139 -149.
Speight ,J.G., 2005, Handbook of Coal Analysis, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken,
New Jersey.
85
Sample Information
Well Sample ID Seam Top
Depth MD (ft)
Bottom Depth MD (ft)
Top Depth Shift
Bottom Depth Shift
RHOB
X127 V-X-127-05 CBM 2 2896.70 2897.90 2896.70 2897.90 1.33
X127 V-X-127-06 CBM 2 2899.70 2901.10 2899.70 2901.10 1.24
X127 V-X-127-Isotherm#3 CBM 2 2901.10 2901.90 2901.10 2901.90 1.24
X127 V-X-127-07 CBM 2 2901.90 2903.50 2901.90 2903.50 1.37
X128 V-X-128-05 CBM 2 2692.05 2693.55 2692.25 2693.75 1.27
X129 V-X-128-06 CBM 2 2693.55 2695.05 2693.75 2695.25 1.39
X202 V-X-202-05 CBM 2 2424.70 2426.70 2424.70 2426.70 1.90
X202 V-X-202-06 CBM 2 2432.90 2434.90 2432.90 2434.90 1.24
X202 V-X-202-07 CBM 2 2437.10 2439.10 2438.10 2440.10 1.22
X203 V-X-203-08 CBM 2 2432.90 2434.90 2433.40 2435.40 1.77
86
Proximate Data
Moisture (%)
Weight (g)
Air Dried Loss
Residual Moisture
Total Moisture
(ARB)
Moisture (As Det.) Vmoisture Moisture
Calc
10.26 3.96 13.81 0.04 0.11
9.70 4.05 13.36 0.04 0.11
115.0 0.18 7.98 8.15 7.96 0.08 0.10
10.62 4.21 14.38 0.04 0.11
143.0 3.91 12.83 16.24 12.80 0.13 0.11
54.0 4.03 12.19 15.73 12.23 0.12 0.09
344.0 4.42 10.97 14.90 10.60 0.11 0.11
392.0 3.07 11.70 14.41 11.48 0.12 0.11
399.0 1.49 12.25 13.56 11.96 0.12 0.11
488.0 1.54 10.20 11.58 10.04 0.10 0.11
87
Ash Content (%) Volatile Matter (%)
A (As Det.) A, (ARB) A, (Dry) Vash Ash Calc VM (As
Det.) VM (ARB) VM (Dry) VM (DAF)
2.90 3.36 0.01 4.93 39.32 45.62 47.20
1.58 1.82 0.01 1.95 39.25 45.30 46.15
7.81 7.79 8.49 0.03 1.68 39.69 39.61 43.12 47.12
3.93 4.59 0.02 9.11 37.06 43.28 45.37
1.37 1.32 1.57 0.01 2.68 39.01 37.47 44.74 45.45
11.37 10.92 12.95 0.04 5.79 35.37 33.96 40.30 46.30
1.93 1.84 2.16 0.01 23.70 41.34 39.35 46.24 47.26
2.45 2.37 2.77 0.01 1.68 42.45 41.04 47.96 49.32
2.14 2.10 2.43 0.01 1.19 42.36 41.59 48.11 49.31
4.47 4.39 4.97 0.02 19.39 43.67 42.92 48.54 51.08
88
Fixed
Carbon (%)
VM VM CALC FC (As Det.) FC (ARB) FC (Dry) FC (DAF) VFC FC CALC
0.61 40.81 43.97 51.02 52.80 0.34 45.38
0.60 41.20 45.81 52.87 53.85 0.36 46.07
0.54 39.37 44.54 44.45 48.39 52.88 0.34 42.82
0.60 40.51 44.63 52.12 54.63 0.35 44.84
0.52 41.28 46.82 44.97 53.69 54.55 0.35 46.20
0.53 38.45 41.03 39.39 46.75 53.70 0.31 41.19
0.54 41.13 46.13 43.91 51.60 52.74 0.34 45.93
0.55 40.97 43.62 42.18 49.28 50.68 0.33 45.65
0.54 41.05 43.54 42.75 49.45 50.69 0.33 45.79
0.56 40.37 41.82 41.10 46.49 48.92 0.32 44.60
89
Calorific Value (Kcal/kg)
Gas Contents on Different Bases (scft/ton) Total Gas Content
Helium Pycnometric
Density (g/cc)
Mean Vitrinite Reflectance
(% Ro) NCV (ARB) ARB
1.34 0.46 182.38
1.33 0.46 200.92
1.37 6260
1.34 0.46 191.49
1.34 0.43 5823 123.83
1.41 0.44 5028 103.56
1.38 5761 56.97
1.39 5874 94.63
1.37 5956 75.62
1.38 121.54
90
Core Description Summary
Black dull and bright coal with no distinct banding, mostly competent, clay and silt present in the form of rare interspersed shaly layers but core was mostly massive coal, one hairline fracture 2.5" from base of core 10° from vertical core axis with calcite mineralization.
Black bright coal, mostly competent, very hard, slightly heavy, possible siltstone at mid core - light gray-tan color area impossible to separate with rock hammer about 3" thick, 2 parallel 1/2" spaced hairline fractures/cleats at bottom of core 10° from vertical core axis, fractures/cleats had calcite mineralization, set of secondary cleats intersecting 1st set at 80° - these cleats were tight with no mineralization.
Black dull (satiny) coal with some bright areas but no distinct banding, competent, slightly heavy, hard, possible weak cleat system with secondary set intersecting at 80°, both sets of cleats were tight with no observed mineralization, no other fracturing observed, few dispersed silty/organic rich layers, bottom area of core was very hard, probably siltstone lithology.
Coal, black, bright, moderate brown streak, blocky cleavage, cleats are observed in moderate-high intensity; Lithotype: Vitrain.
Coal, black, bright, moderate brown streak, blocky - concoidal cleavage, medium hardness, cleats are observed in low-moderate intensity, pyrites and ambers are commonly observed at the middle section.; Lithotype: Vitrain.
Coal, black, bright, moderate brown streak, blocky - concoidal cleavage, medium hardness, cleats are observed in low-moderate intensity, Amber observed at bottom section.; Lithotype: Vitrain.
Coal, black, bright, moderate brown streak, blocky - concoidal cleavage, medium hardness, cleats are observed: low-moderate intensity, Amber observed in bottom section; Lithotype: Vitrain.