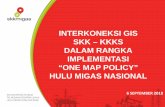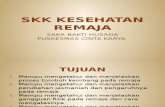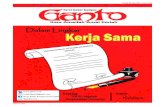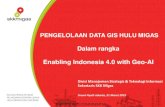SKK MIGAS
-
Upload
asharizuprin -
Category
Documents
-
view
31 -
download
0
Transcript of SKK MIGAS

Mencermati Cost Recovery
Cost Recovery merupakan topik yang paling sering dibicarakan di industri migas. Pertanyaan yang terus berulang adalah; mengapa harus ada cost recovery, dan apakah nilainya tak bisa diturunkan?--Cost Recovery atau pengembalian biaya operasi sudah merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Cost Recovery ada karena proyek hulu migas merupakan bisnis negara, dan negara perlu dana talangan untuk menjalankan usaha ini. Dana talangan diperlukan karena bisnis ini butuh investasi besar dan berisiko tinggi. Dalam Kontrak Bagi Hasil, Production Sharing Contract (PSC), yang digunakan industri hulu migas Indonesia, sistem dana talangan ini melindungi negara dari risiko eksplorasi, karena cost recovery hanya akan dilakukan bila cadangan komersial ditemukan.
Hal yang tidak banyak diketahui publik adalah; pengembalian biaya operasi atau cost recovery tidak hanya terdapat pada PSC, tetapi juga pada jenis kontrak-kontrak hulu migas lainnya, yaitu sistem service contract dan sistem konsesi. Service contract atau kontrak jasa mengacu kepada kontrak antara pemerintah dan perusahaan migas yang dikaitkan dengan jasa kegiatan eksplorasi, pengembangan, dan produksi migas. Pada sistem ini kontraktor menerima pembayaran fee atas jasa yang mereka berikan. Bila dalam PSC, setelah cost recovery, kontraktor memperoleh profit share dalam bentuk natura (in kind), dalam service contract perusahaan menerima service fee yang umumnya dalam bentuk uang. Tentunya, komponen pengembalian biaya operasi juga ada dalam sistem ini, tapi istilahnya bukan cost recovery, melainkan reimbursement.
Pada sistem konsesi, perusahaan migas berhak atas produksi migas, sementara negara menerima pembayaran royalti, berupa persentase dari pendapatan bruto, dan pajak. Nah, pada sistem ini pengembalian biaya operasi akan dicatat sebagai biaya dalam rangka perhitungan sebelum pajak. Artinya, pengembalian biaya tetap ada, namun istilahnya juga bukan cost recovery, tetapi cost deduction.
Dari pemaparan di atas, terlihat jelas bahwa pengembalian biaya operasi terjadi pada semua jenis kontrak hulu migas. Hal yang membedakan cost recovery pada PSC dengan pada sistem kontrak lain, terutama sistem konsesi, adalah pada PSC, perusahaan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemerintah yang berwenang untuk dapat memperoleh pengembalian biaya operasi tersebut. Artinya, pada sistem cost recovery dalam PSC, pengawasan pemerintah jauh lebih ketat dibandingkan dengan sistem konsesi.
Lalu, bagaimana dengan kemungkinan penggelembungan atau mark up pengembalian biaya operasi yang dapat mengurangi penerimaan negara dari industri hulu migas? Karena cost recovery hakikatnya ada pada semua sistem kontrak, kemungkinan mark up bisa juga terjadi pada sistem mana pun. Hanya saja, dengan sistem PSC kecenderungan itu seharusnya lebih dapat dihindari mengingat mekanisme pengawasan yang relatif lebih ketat.
Pertanyaan berikutnya, dengan adanya pengawasan cost recovery dalam PSC, mengapa besarannya tidak diturunkan saja? Perlu diingat, menurunkan cost recovery dapat berakibat kontra-produktif bagi upaya meningkatkan produksi dan cadangan migas nasional. Bagi perusahaan migas, cara paling mudah menurunkan cost recovery secara signifikan adalah dengan menunda pengembangan lapangan, mengurangi pemeliharaan, membatalkan rencana eksplorasi, dan lain-lain. Hal yang akan terjadi adalah dalam jangka pendek cost recovery akan turun, tetapi dalam jangka panjang produksi dan cadangan migas akan terus anjlok. Penghematan dalam jumlah kecil bisa saja akan menyebabkan kehilangan penerimaan negara dan pasokan energi dengan nilai yang lebih besar.
Intinya, menurunkan besaran cost recovery bukanlah hal paling penting untuk dilakukan karena membatasi cost recovery identik dengan membatasi investasi. Hal yang paling penting untuk dilakukan adalah bagaimana memperkuat pengawasan supaya program dan anggaran yang dikeluarkan oleh kontraktor sudah sesuai dengan kaidah keteknikan, efektif, dan efisien. Itulah tugas semua komponen negara Republik Indonesia untuk mewujudkan pengawasan seperti ini.

Mengendalikan Cost Recovery
Cost Recovery terlanjur dipakai untuk menjelaskan pengembalian biaya operasi pada industri hulu migas. Bagaimana negara mengendalikan pengembalian biaya operasi atau Cost Recovery ini?--Hal pertama yang penting untuk diketahui pada industri hulu minyak dan gas bumi (migas) adalah bahwa biaya operasi tidak dikembalikan pemerintah dalam bentuk dana atau uang, tapi dalam bentuk produksi migas. Artinya, tidak ada aliran dana yang dikeluarkan secara fisik, baik oleh pemerintah -- melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)-- maupun oleh Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Pengembalian itu langsung dipotong dari produksi migas saat perhitungan jatah negara versus jatah perusahaan migas yang menjadi kontraktor kontrak kerja sama (Kontraktor KKS), misalnya PT Pertamina EP, PT Chevron Pacific Indonesia, dan Total E&P Indonesia, dilakukan.Namun, negara sadar pengembalian biaya operasi jadi salah satu faktor pengurang penerimaan negara sehingga perlu dikendalikan dan diawasi. SKK Migas sebagai wakil negara dalam kontrak berperan dominan dalam pengendalian dan pengawasan tersebut. Layaknya organisasi modern, pengendalian dan pengawasan ini tidak semata-mata mengandalkan pengawasan fisik, tetapi, lebih penting dari itu adalah memastikan setiap proses bisnis memiliki pengendalian internal (internal control). Pengendalian internal ini harus ada di SKK Migas, dalam interaksi bisnis SKK Migas dan Kontraktor KKS, maupun di Kontraktor KKS. SKK Migas sendiri memiliki pedoman tata kerja yang baku untuk setiap titik simpul-simpul interaksi dengan Kontraktor KKS.Pada prinsipnya, SKK Migas melakukan pengendalian dan pengawasan dalam tiga tahapan, yaitu saat awal akan terjadinya biaya (pre audit); saat eksekusi biaya dan pelaksanaan pekerjaan (current audit); dan terakhir, setelah biaya terjadi dan pekerjaan selesai dilakukan (post audit).Pre audit dilakukan melalui pengawasan terhadap perencanaan yang dilakukan Kontraktor KKS. Pengawasan perencanaan antara lain dilakukan melalui persetujuan rencana pengembangan lapangan atau Plan of Development (POD) yang mencerminkan rencana jangka panjang Kontraktor KKS. Pengawasan juga dilakukan pada saat penyusunan program kerja dan anggaran tahunan, yaitu melalui persetujuan Work Program and Budget (WP&B), dan juga ketika anggaran tersebut dilaksanakan dalam proyek-proyek. Pengawasan proyek itu dilakukan saat pertama kali kontraktor menyampaikan rencana proyek yang dituangkan dalam Authorization for Expenditure (AFE) yang juga mensyaratkan persetujuan SKK Migas.Current audit dilakukan melalui pengawasan atas mekanisme pengadaan dan pelaksanaan proyek. Pengawasan terhadap pengadaan dilakukan dengan menerapkan pedoman tata kerja yang menjadi acuan bagi Kontraktor KKS dalam pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, untuk proyek-proyek besar, pengawasan dilakukan oleh unit khusus yang melakukan monitor dan pengawasan secara intensif.Post audit dilaksanakan dengan menggunakan prosedur auditing yang secara umum digunakan. Kontraktor KKS secara internal melakukan audit atas laporan keuangan mereka. Sedangkan audit terhadap Kontraktor KKS yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah dilakukan oleh SKK Migas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Direktorat Jenderal Pajak. Bagaimana jika setelah post audit dilakukan terdapat temuan pengembalian biaya operasi yang tidak seharusnya? Kelebihan pengembalian ini akan dikoreksi pada proses bagi hasil berikutnya yaitu dengan mengurangi bagian Kontraktor KKS sebesar kelebihan pengembalian biaya operasi tersebut. Hal yang sama berlaku apabila pengembalian justru lebih rendah dari seharusnya. Jatah pemerintah pada bagi hasil berikutnya akan berkurang sebesar kekurangan pengembalian. Mekanisme koreksi ini dikenal dengan istilah over/under lifting. Hal ini dapat diterapkan dalam industri hulu migas karena siklus bisnisnya yang panjang yaitu selama kontrak berlaku atau 30 tahun.Tata kelola untuk mengendalikan pengembalian biaya operasi atau Cost Recovery sudah dibangun sebagai bagian upaya memaksimalkan penerimaan hulu migas bagi negara. Tentu saja ruang perbaikan masih terbuka. Input yang konstruktif hanya bisa dihasilkan dari pemahaman yang benar dan menyeluruh tentang kegiatan usaha hulu migas di Indonesia.

Cost Recovery Industri Hulu Migas
Isu Cost Recovery sering mengundang perdebatan pada industri hulu migas. Mengapa perlu ada Cost Recovery? mengapa Cost Recovery meningkat tapi produksi menurun?
--
Kontrak Bagi Hasil atau Production Sharing Contract (PSC) yang digunakan dalam industri hulu minyak dan gas bumi (migas) sebenarnya tidak mengenal istilah Cost Recovery. Salah satu klausul dalam PSC memang menyebutkan bahwa “Kontraktor akan memperoleh kembali penggantian atas biaya operasi dengan diambilkan dari hasil penjualan atau penyerahan lainnya dari jumlah Minyak dan Gas Bumi senilai dengan biaya operasi, yang diproduksi dan disimpan dan tidak digunakan dalam operasi minyak dan gas bumi”. Frasa yang menyatakan “memperoleh kembali penggantian biaya operasi” ini yang oleh banyak pihak didefinisikan sebagai cost recovery.
Pertanyaan mengapa cost recovery atau pengembalian biaya operasi perlu ada dalam industri hulu migas didasari pemahaman yang keliru dalam melihat industri ini. Penanya mungkin mengira bahwa kegiatan usaha hulu migas yang dilaksanakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS), seperti PT Pertamina EP, PT Cevron Pacific Indonesia, dan Total E&P Indonesie, adalah bisnis korporasi swasta sehingga biaya operasi tidak perlu diganti.
Pemahaman ini tentu saja keliru karena sesungguhnya bisnis hulu migas adalah proyek negara, sedangkan perusahaan-perusahaan itu hanyalah kontraktor negara yang bekerja mencari dan memproduksi migas untuk dan atas nama negara. Pemerintah adalah pemegang kuasa pertambangan dan para kontraktor ini yang melakukan pekerjaan sekaligus menyediakan dana talangan untuk kegiatan itu.
Dalam bisnis hulu migas, cost recovery atau pengembalian atas biaya operasi atau dana talangan ini hanya akan dilakukan bila cadangan migas yang ditemukan ekonomis. Bila kegiatan eksplorasi tidak menemukan cadangan yang ekonomis, dana talangan tidak akan dikembalikan. Mekanisme ini sesungguhnya membantu membebaskan pemerintah dari paparan resiko besar pada tahapan eksplorasi.
Lalu mengapa Cost Recovery meningkat sementara produksi migas menurun? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan menelaah karakteristik bisnis hulu migas. Pada bisnis lain, misalnya saja usaha manufaktur, penambahan investasi pada tahun berjalan mungkin akan langsung menghasilkan output lebih besar pada waktu yang bersamaan. Kondisi seperti ini tidak terjadi pada industri hulu migas yang memiliki siklus bisnis panjang, yaitu satu periode kontrak sekitar 30 tahun.
Pada bisnis hulu migas, pengembalian biaya pada tahun ini tidak akan diikuti dengan kenaikan produksi pada tahun yang sama, karena biaya yang digantikan adalah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelum terjadinya kegiatan produksi dan penjualan migas. Termasuk ke dalam kegiatan ini adalah kegiatan eksplorasi yang bisa saja sudah dimulai lima tahun sebelum lapangan berproduksi. Pengeluaran dan biaya sudah terjadi, sementara baru lima tahun kemudian dapat dibebankan sebagai biaya dan diakui sebagai Cost Recovery.
Meskipun lapangan sudah memasuki fase produksi, pengeluaran investasi untuk meningkatkan produksi pada lapangan itu tidak serta merta berujung pada naiknya produksi pada tahun berjalan karena butuh waktu untuk melakukan pengeboran, membangun fasilitas, dan lain-lain. Di samping itu, fasilitas produksi yang sudah ada tetap memerlukan biaya perawatan untuk mempertahankan kinerjanya, sementara di sisi lain sudah menjadi sifat alami bahwa produksi pada lapangan-lapangan migas yang tua akan terus menurun. Jadi intinya, ada lag time atau perbedaan waktu antara pengeluaran untuk membiayai operasional dan terjadinya produksi migas.
Cara yang fair untuk melihat kinerja sebuah proyek migas adalah dengan mengevaluasi kinerja selama satu siklus bisnisnya secara penuh, yaitu selama periode kontrak, bukan dengan pendekatan jangka pendek. Selain itu, pemahaman yang akurat mengenai sifat alami bisnis ini juga perlu dimiliki.

Penggantian Cost Recovery memang perlu dikendalikan untuk memastikan negara menerima manfaat maksimal dari kegiatan hulu migas. Tapi, demi berlangsungnya iklim investasi yang kondusif, kritik atas hal ini perlu didasari oleh pemahaman yang benar terlebih dahulu.

Cost Recovery:Pengurang Penerimaan Negara vs Investasi
Cost recovery banyak dipersoalkan karena dianggap sebagai kehilangan penerimaan negara. Padahal cost recovery adalah investasi yang memungkinkan kegiatan usaha hulu migas menghasilkan penerimaan negara.
--
Sesuai dengan konstitusi, kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas) merupakan bisnis negara. Layaknya bisnis pada umumnya, proyek hulu migas juga memerlukan investasi sebagai modal untuk menjalankan eksplorasi dan produksi. Mengingat kegiatan ini selain memerlukan investasi yang besar juga memiliki risiko yang tinggi, negara kemudian mengundang investor untuk menjadi kontraktor yang bekerja bagi negara melakukan kegiatan operasi industri hulu migas.
Kerja sama ini disepakati melalui mekanisme Kontrak Bagi Hasil, atau Production Sharing Contract (PSC), yang mensyaratkan kontraktor untuk menyediakan investasi, skill dan teknologi untuk menggarap wilayah kerja migas. Pada saat wilayah itu telah berproduksi, negara dan kontraktor akan berbagi keuntungan setelah penerimaan negara dikurangi dengan beberapa faktor pengurang, termasuk pengembalian biaya operasi atau cost recovery tersebut.
Nah, cost recovery inilah yang kemudian banyak dipersoalkan karena dianggap sebagai kehilangan penerimaan negara akibat diambil oleh kontraktor. Padahal, cost recovery sejatinya adalah investasi yang tanpanya tidak mungkin kegiatan usaha hulu migas bisa berjalan dan menghasilkan penerimaan negara.
Cost recovery yang meningkat kerap menuai kritik, padahal bila dicermati, investasi yang terus meningkat setiap tahunnya menjadi salah satu faktor pendukung peningkatan penerimaan negara dari sektor hulu migas. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2009, besaran cost recovery adalah US$10,109 miliar, sedangkan penerimaan negara mencapai US$19,950 miliar. Pada 2010, nilai cost recovery menjadi US$11,763 miliar, atau meningkat 16,36 persen, tapi penerimaan negara meningkat lebih besar, yaitu dari US$19,950 miliar menjadi US$26,497 miliar, atau naik 32,82 persen. Tren yang sama terjadi pada 2011. Besaran cost recovery naik menjadi US$15,216 miliar, atau meningkat 29,35 persen, sedangkan penerimaan negara naik hingga mencapai US$35,850 atau meningkat 35,3 persen.
Selain menghasilkan penerimaan negara, investasi ini juga memiliki multiplier effect karena dana yang sangat besar itu digunakan di dalam negeri sehingga mendorong majunya sektor-sektor lain di luar industri hulu migas. Sebagai gambaran, nilai seluruh komitmen pengadaan barang dan jasa bulan Januari-September 2013 mencapai US$8,813 miliar dengan persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 54,18 persen (cost basis). Kegiatan pengadaan barang dan jasa industri hulu migas ini juga memberikan efek positif bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari tahun 2010 sampai Agustus 2013, pengadaan barang dan jasa industri hulu migas yang dilakukan melalui BUMN mencapai US$3,02 miliar dengan persentase TKDN sebesar 73,46 persen.
Uraian di atas jelas memperlihatkan bahwa penggantian biaya operasi (cost recovery) tidak bisa semata-mata dilihat sebagai pengurang penerimaan negara, tapi adalah investasi yang justru mendukung realisasi penerimaan negara dari sektor ini sekaligus menjadi multiplier effects pada ekonomi nasional.
Tentu saja, penggantian biaya operasi ini harus diawasi dan dikendalikan. Semangatnya, menghindari pembebanan yang tidak tepat, bukan semata-mata untuk memangkas cost recovery. Pengurangan cost recovery antara lain akan berujung kepada pengurangan anggaran eksplorasi, pengeboran pengembangan dan workover, hingga pemangkasan biaya operasi produksi. Ini tentunya akan berdampak pada produksi migas nasional. Produksi dari lapangan yang sudah ada terancam turun dan produksi dari lapangan baru terancam mundur. Pada akhirnya, pembatasan biaya operasi tidak hanya akan membahayakan realisasi penerimaan negara, tetapi juga kelangsungan ketersediaan migas di Indonesia.