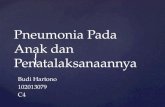Skenario B Blok 18 Tahun 2013
-
Upload
retno-tharra -
Category
Documents
-
view
216 -
download
45
description
Transcript of Skenario B Blok 18 Tahun 2013
LAPORAN TUTORIAL
SKENARIO B BLOK 18
Disusun oleh :
Kelompok 9
Tatia Indira 04111401003
Anantya Dianty S 04111401004
Ghea Duandiza 04111401008
Keidya Twintananda 04111401022
Novi Auliya Dewi 04111401025
Ali Zainal Abidin 04111401026
Amir Ibnu Hazbullah 04111401032
Yusti Desita Indriani 04111401042
David Wijaya 04111401052
Arie Wahyudi Wijaya 04111401071
Kristian Sudana Hartanto 04111401085
Nur Eqbariah Baharuden 04111401099
Tutor : dr. Yuniza
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya penulis
dapat menyelesaikan laporan tutorial skenario B blok 18 sebagai tugas kompetensi kelompok.
Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita, nabi besar Muhammad SAW
beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.
Penulis menyadari bahwa laporan tutorial ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan di masa mendatang.
Dalam penyelesaian laporan tutorial ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan saran.
Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :
1. Allah SWT.
2. Kedua orang tua yang memberi dukungan materil maupun spiritual.
3. dr.Yuniza selaku tutor.
4. Teman-teman sejawat dan seperjuangan.
5. Semua pihak yang membantu penulis.
Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala atas segala amal yang diberikan kepada
semua orang yang telah mendukung penulis dan semoga laporan tutorial ini bermanfaat tidak
hanya untuk penulis tetapi juga untuk orang lain dalam perkembangan ilmu pengetahuan di masa
yang akan datang.
Palembang, Juni 2013
Penulis
2
DAFTAR ISI
KATAPENGANTAR............................................................. .........................2
DAFTAR ISI..................................................................................................3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang......................................................................................4
1.2 Maksud dan Tujuan...............................................................................4
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Data Tutorial.............................................................................................5
2.2 Skenario Blok11........................................................................................6
2.3 Paparan
I. Klarifikasi Istilah.........................................................................................7
II. Identifikasi Masalah....................................................................................8
III. Analisis Masalah........................................................................................9
IV. Kerangka Konsep......................................................................................34
V. Kesimpulan...............................................................................................35
VI. Learning Issues dan Keterbatasan Pengetahuan.............................................35
BAB III
SINTESIS
3.1 Anatomi dan fisiologi traktus urinarius ........................................................36
3.2 ISK...............................................................................................................43
3.3 Proteus mirabilis..........................................................................................44
DAFTAR PUSTAKA..................................................................................... 48
3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Blok Nefro-Urologi adalah blok 18 pada semester 4 dari Kurikulum Berbasis Kompetensi
(KBK) Pendidikan Dokter Umum Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang.
Pada kesempatan ini dilaksanakan tutorial studi kasus sebagai bahan pembelajaran untuk
menghadapi tutorial yang sebenarnya pada waktu yang akan datang
1.2 Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan dari materi praktikum tutorial ini, yaitu :
1. Sebagai laporan tugas kelompok tutorial yang merupakan bagian dari sistem pembelajaran
KBK di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang.
2. Dapat menyelesaikan kasus yang diberikan pada skenario dengan metode analisis dan
pembelajaran diskusi kelompok.
3. Tercapainya tujuan dari metode pembelajaran tutorial dan memahami konsep dari skenario
ini.
4
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Data Tutorial
Tutorial Skenario B
Tutor : dr. Yuniza
Moderator : Arie Wahyudi Wijaya
Sekretaris papan : Amir Ibnu Hizbullah
Sekretaris meja : Novi Auliya Dewi
Waktu : Senin, 17 Juni 2013
Rabu, 19 Juni 2013
Peraturan tutorial : 1. Alat komunikasi dinonaktifkan.
2. Semua anggota tutorial harus mengeluarkan pendapat dengan
cara mengacungkan tangan terlebih dahulu dan apabila telah
dipersilahkan oleh moderator.
3. Tidak diperkenankan meninggalkan ruangan selama proses
tutorial berlangsung.
4. Tidak diperbolehkan makan dan minum.
5
2.2 Skenario B Blok 18
Anisa, usia 10 bulan, dibawa ibunya ke klinik anak karena panas tinggi sejak 2 hari yang
lalu. Tidak ada keluhan batuk atau pilek maupun diare. Sejak kira-kira 1 minggu sebelumnya
anak sering tampak kesakitan setiap mau buang air kecil. Ibunya juga mengeluhkan daerah
sekitar kemaluan yang tampak makin merah ( ruma popok ) sejak 2 minggu yang lalu. Riwayat
sejak bayi ibu penderita selalu memakaikan popok sekali pakai dan biasanya diganti 2 kali pada
siang hari dan hanya 1 kali pada malam hari.
Pada pemeriksaan fisik:
Anak tampak sakit berat, suhu 39,50 C, nadi 100x/menit, pernafasan 36 x/menit, TD 90/60
mmHg, BB = 10 kg, TB = 75 cm.
Pemeriksaan paru dan jantung dalam batas normal.
Pemeriksaan abdomen datar, lemas, hepar/lien tidak teraba, tidak teraba massa, bising usus
normal, nyeri ketok costovertebral dan nyeri tekan suprapubik sulit dinilai.
Regio anogenital: hiperemis dan ruam makulopapular di area yang ditutupi popok
Hasil pemeriksaan laboratorium rutin:
Hematologi: Hb: 11 g/dl, lekosit: 23.000/mm3, Hitung jenis 0/1/4/80/13/2. LED 40 mm/jam.
Urinalisis: warna kuning, agak keruh, lekosit penuh, eritrosit, 5-6/lpb, lekosit esterase positif,
nitrit positif.
Hasil pemeriksaan lanjutan:
Kultur urin: Proteus mirabilis >100.000/ul, sensitive dengan cotrimoxazole dan cefotaxime (cara
pengambilan dengan urin pancar tengah/mid stream)
USG TUG: pembengkakan parenkim ginjal serta batas kortikomedulla tidak jelas
6
2.3 Paparan
I. Klarifikasi Istilah
No
.
Istilah Pengertian
1 Hiperemis Pembengkakan, ekses darah pada bagian tubuh tertentu.
2 Costovertebral Berkenaan dengan iga dan vertebra.
3 Anogenital Berhubungan dengan daerah anal dan genitalia.
4 Ruam makulopapular Bintik-bintik dan benjolan kecil kemerahan pada kulit.
5 Leukosit esterase Enzim yang di temukan pada sel darah putih merupakan
pertanda peradangan yang umum nya disebabkan oleh ISK.
6 Nitrit Setiap garam dari asam nitrit.
7 Proteus mirabilis Spesies yang paling sering di isolasi dari materi klinis manusia.
Penyebab tersering dari ISK juga dapat di temukan di tanah
dan sampah.
8 Cotrimoxazole Campuran trimetropin dan sulfametoksazole, suatu anti
bacterial yang terutama digunakan dalam pengobatan infeksi
saluran kemih dan pneumonia pneumosistis.
9 Cefotaxime Antibiotik sefalosporin semi sintetis berspektrum luas yang
aktif terhadap banyak organism yang telah resisten terhadap
antibiotic penisilin, sefalosporin, dan amino glikosida
10 Urine pancar tengah Dimana aliran pertama urin di buang dan urin selanjutnya di
tampung.
11 Kortikomedulla Daerah sekitar korteks dan medulla pada daerah parenkim
ginjal.
7
II. Identifikasi Masalah
No Pernyataan Konsen1 Anisa, usia 10 bulan, dibawa ibunya ke klinik anak
karena panas tinggi sejak 2 hari yang lalu. VVV
2 Sejak kira-kira 1 minggu sebelumnya anak sering tampak kesakitan setiap mau buang air kecil. VV
3 Ibunya juga mengeluhkan daerah sekitar kemaluan yang tampak makin merah ( ruma popok ) sejak 2 minggu yang lalu.
VV
4 Riwayat sejak bayi ibu penderita selalu memakaikan popok sekali pakai dan biasanya diganti 2 kali pada siang hari dan hanya 1 kali pada malam hari.
VV
5 Pada pemeriksaan fisik:Anak tampak sakit berat, suhu 39,50 C, nadi 100x/menit, pernafasan 36 x/menit, TD 90/60 mmHg, BB = 10 kg, TB = 75 cm.Pemeriksaan paru dan jantung dalam batas normal.Pemeriksaan abdomen datar, lemas, hepar/lien tidak teraba, tidak teraba massa, bising usus normal, nyeri ketok costovertebral dan nyeri tekan suprapubik sulit dinilai.Regio anogenital: hiperemis dan ruam makulopapular di area yang ditutupi popok
V
6Hasil pemeriksaan laboratorium rutin:Hematologi: Hb: 11 g/dl, lekosit: 23.000/mm3, Hitung jenis 0/1/4/80/13/2. LED 40 mm/jam.Urinalisis: warna kuning, agak keruh, lekosit penuh, eritrosit, 5-6/lpb, lekosit esterase positif, nitrit positif.
V
7 Hasil pemeriksaan lanjutan:Kultur urin: Proteus mirabilis >100.000/ul, sensitive dengan cotrimoxazole dan cefotaxime (cara pengambilan dengan urin pancar tengah/mid stream)USG TUG: pembengkakan parenkim ginjal serta batas kortikomedulla tidak jelas
V
8
III. Analisis Masalah
1) Anisa, usia 10 bulan, dibawa ibunya ke klinik anak karena panas tinggi sejak 2 hari yang
lalu.
a. Apa Etiologi dan Mekanisme dari panas tinggi pada kasus ini ?
Etiologi demam :
Demam dapat disebabkan oleh faktor infeksi ataupun faktor non infeksi.
- Demam akibat infeksi bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur,
ataupun parasit. Infeksi bakteri yang pada umumnya menimbulkan demam
pada anak-anak antara lain pneumonia, bronkitis, osteomyelitis,
appendisitis, tuberculosis, bakteremia, sepsis, bakterial gastroenteritis,
meningitis, ensefalitis, selulitis, otitis media, infeksi saluran kemih, dan
lain-lain (Graneto, 2010). Infeksi virus yang pada umumnya menimbulkan
demam antara lain viral pneumonia, influenza, demam berdarah dengue,
demam chikungunya, dan virus-virus umum seperti H1N1 (Davis, 2011).
Infeksi jamur yang pada umumnya menimbulkan demam antara lain
coccidioides imitis, criptococcosis, dan lain-lain (Davis, 2011). Infeksi
parasit yang pada umumnya menimbulkan demam antara lain malaria,
toksoplasmosis, dan helmintiasis (Jenson & Baltimore, 2007).
- Demam akibat faktor non infeksi dapat disebabkan oleh beberapa hal
antara lain faktor lingkungan (suhu lingkungan yang eksternal yang terlalu
tinggi, keadaan tumbuh gigi, dll), penyakit autoimun (arthritis, systemic
lupus erythematosus, vaskulitis, dll), keganasan (Penyakit Hodgkin,
Limfoma nonhodgkin, leukemia, dll), dan pemakaian obat-obatan
(antibiotik, difenilhidantoin, dan antihistamin) (Kaneshiro & Zieve, 2010).
Selain itu anak-anak juga dapat mengalami demam sebagai akibat efek
samping dari pemberian imunisasi selama ±1-10 hari (Graneto, 2010). Hal
lain yang juga berperan sebagai faktor non infeksi penyebab demam
adalah gangguan sistem saraf pusat seperti perdarahan otak, status
9
epileptikus, koma, cedera hipotalamus, atau gangguan lainnya (Nelwan,
2009).
Mekanisme demam :
Proses terjadinya demam dimulai dari stimulasi sel-sel darah putih (monosit,
limfosit, dan neutrofil) oleh pirogen eksogen baik berupa toksin, mediator
inflamasi, atau reaksi imun. Sel-sel darah putih tersebut akan mengeluarkan
zat kimia yang dikenal dengan pirogen endogen (IL-1, IL-6, TNF-α, dan IFN).
Pirogen eksogen dan pirogen endogen akan merangsang endotelium
hipotalamus untuk membentuk prostaglandin (Dinarello & Gelfand, 2005).
Prostaglandin yang terbentuk kemudian akan meningkatkan patokan termostat
di pusat termoregulasi hipotalamus. Hipotalamus akan menganggap suhu
sekarang lebih rendah dari suhu patokan yang baru sehingga ini memicu
mekanisme-mekanisme untuk meningkatkan panas antara lain menggigil,
vasokonstriksi kulit dan mekanisme volunter seperti memakai selimut.
Sehingga akan terjadi peningkatan produksi panas dan penurunan
pengurangan panas yang pada akhirnya akan menyebabkan suhu tubuh naik
ke patokan yang baru tersebut (Sherwood, 2001).
b. Apa Hubungan usia dengan jenis kelamin pada kasus ini?
10
- Jenis kelamin :
Lebih sering terjadi pada perempuan sebab urethra pada perempuan lebih
pendek dan lebih dekat ke anus dibandingkan laki - laki. Hal ini membuat
wanita lebih sering mengalami ISK dibanding laki – laki
- Usia :
Lebih sering pada bayi dan usia >65 tahun. Pada bayi, sering terjadi ISK
karena bayi masih belum mengerti dan belum dapat menjaga kebersihannya
sendiri. Selain itu, pemakaian popok pada bayi dapat membuat kulit bayi
mengalami kontak dengan iritan (urin dan feses) dan bakteri (banyak dalam
feses, seperti E. Coli dan Proteus sp.) dalam waktu yang lebih lama. Hal ini
membuat resiko untuk mengalami ISK meningkat.
2) Sejak kira-kira 1 minggu sebelumnya anak sering tampak kesakitan setiap mau buang air
kecil.
a. Apa etiologi dan mekanisme disuria pada kasus ini ?
Etiologi disuria :
- Infeksi, misalnya pyelonephritis, cystitis, prostatitis, urethritis, cervicitis,
epididymo-orchitis, vulvovaginitis.
- Kondisi Hormonal, misalnya hypoestrogenism, endometriosis.
- Malformasi, misalnya obstruksi leher vesica urinaria (misalnya benign
prostatic hyperplasia), urethral strictures atau diverticula.
- Neoplasma, misalnya tumor sel renal, vesica urinaria, prostat,
vagina/vulva, dan kanker penis
- Peradangan, misalnya spondyloarthropathies, efek samping obat, penyakit
autoimun.
- Trauma, misalnya karena pemasangan kateter, “honeymoon” cystitis
- psychogenic, misalnya somatization disorder, major depression, stress atau
anxietas, hysteris.
11
Dua pertiga infeksi traktus urinarius terbukti disebabkan oleh Escherichia coli.
Penyebab lain yang kurang umum termasuk Staphylococcus saprophyticus (15%),
Proteus mirabilis (10%),Staphyloccus aureus (5%), Enterococcus sp. (3%), dan
Klebsiella sp. (3%)
Urethra lebih umum terinfeksi oleh organism seperti Neisseria gonorrhoeae atau
Chlamidia trachomatis. Pathogen lain termasuk Ureaplasma urealyticum,
Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, dan HSV. Infeksi yang jarang
mengakibatkan disuria termasuk adenovirus, herpesvirus, mumps virus, dan
parasit tropis Schistosoma haematobium.
Mekanisme :
Pada pasien ini, orang tuanya menggunakan popok sekali pakai dan jarang
mengganti popok. Hal ini membuat urine dan feses (bersifat iritan) yang ada di
popok berkontak lebih lama dengan kulit bayi, khususnya pada daerah anogenital.
Hal ini akan menimbulkan iritasi pada lapisan kulit dan membuat daya tahan kulit
menurun. Akibatnya, patogen akan lebih mudah tumbuh dan berkembang biak
pada daerah tersebut. Hal ini membuat resiko pasien untuk mengalami ISK
menjadi lebih besar. Rute infeksi yang mungkin adalah ascending infection
melalui urethra ke buli lalu ke ginjal. Adanya infeksi pada saluran kemih inilah
yang kemudian menimbulkan nyeri saat berkemih (disuria).
b. Apa hubungan disuria dengan keluhan utama ?
Hubungan keluhan dari disuria pada 1 minggu yg lalu dengan demam 2 hari
yg lalu menunjukkan jika penyebaran infeksi terjadi secara ascending . Awalnya
terjadi infeksi mikroorganisme pada uretra,kemudian masuk ke dalam vesica
urinaria , dan bermultiplikasi dan menempel di vesica urinaria,infeksi pada vesica
urinaria tersebut akan mengakibatkan iritasi dan spasme otot polos sehingga
timbul keluhan berupa disuria , lalu MO tersebut menuju ke ureter dan ginjal.
Infeksi pada ginjal selanjutnya akan menimbulkan keluhan demam tinggi .
12
3) Ibunya juga mengeluhkan daerah sekitar kemaluan yang tampak makin merah ( ruam
popok ) sejak 2 minggu yang lalu.
a. Apa etiologi dan mekanisme dari ruam ?
Etiologi dan mekanisme:
Beberapa faktor penyebab terjadinya ruam popok ( diaper rash, diaper dermatitis,
napkin dermatitis ), antara lain:
1. Kebersihan kulit bayi dan pakaiaan bayi yang tidak terjaga, misalnya jarang
ganti popok setelah bayi atau anak kencing
2. Udara / Suhu lingkungan yang terlalu panas/lembab
3. Akibat mencret
4. Reaksi kontak terhadap karet , plastic dan detergen , misalnya pampers
5. Gangguan pada kelenjar keringat di area yang tertutup popok.
6. Iritasi atau gesekan antara popok dengan kulit.
7. Infeksi mikro-organisme (terutama infeksi jamur dan bakteri)
8. Alergi bahan popok.
Mekanisme :
Pada pasien ini, orang tuanya menggunakan popok sekali pakai dan jarang
mengganti popok. Hal ini membuat urine dan feses (bersifat iritan) yang ada di
popok berkontak lebih lama dengan kulit bayi, khususnya pada daerah anogenital.
Efek sitotosik lokal langsung dari bahan iritan baik fisika maupun kimia, yang
bersifat tidak spesifik, pada sel-sel epidermis akan menimbulkan respon
peradangan pada dermis dalam waktu dan konsentrasi yang cukup. Bahan iritan
merusak lapisan tanduk, denaturasi keratin, menyingkirkan lemak lapisan tanduk
dan mengubah daya ikat air pada kulit. Kebanyak bahan iritan merusak membran
13
lemak keratinosit tetapi sebagian dapat menembus membran sel dan merusak
lisosom, mitokondria atau komplemen inti.
Kerusakan membran mengaktifkan fosfolipase dan menstimulasi pelepasan asam
arakidonat (AA), diasilgliserida (DAG), faktor aktivasi platelet, dan inositida
(IP3).
Asam arakidonat diubah menjadi prostaglandin (PG) dan leukotrien (LT). PG dan
LT menginduksi vasodilatasi, dan meningkatkan permeabilitas vaskuler sehingga
mempermudah transudasi komplemen dan kinin. PG dan LT juga bertindak
sebagai kemotraktan kuat untuk limfosit dan neutrofil, serta mengaktifasi sel mast
melepaskan histamin, LT dan PG lain, dan PAF (platelet activating factor),
sehingga memperkuat perubahan vaskuler. Hal ini membuat bagian kulit yang
mengalami iritasi tampak lebih merah (ruam).
Diasilgliserol dan second messenger lain menstimulasi ekspresi gen dan sintesis
protein, misalnya interleukin-1 (IL-1) dan granulocyte macrophage-colony
stimulating factor (GM-CSF). IL-1 mengaktifkan sel T-helper mengeluarkan IL-
2. Pada kontak dengan iritan, keratinosit juga melepaskan TNF-α, suatu sitokin
proinflamasi yang dapat mengaktifasi sel T, makrofag dan granulosit,
menginduksi ekspresi molekul adesi sel dan pelepasan sitokin.
Rentetan kejadian tersebut menimbulkan gejala peradangan klasik di tempat
terjadinya kontak di kulit berupa eritema, edema, panas, dan nyeri. Efek dari iritan
merupakan concentration-dependent, sehingga hanya mengenai tempat primer
kontak.
b. Apa makna klinis dari kronologis keluhan (ruam – disuria- demam ) ?
Menunujukkan kronologis perjalanan penyakit ,dimulai akibat penggunaan popok
yang tidak tepat pada kasus ini akan menyebabkan timbulnya ruam , akibat dari
bagian anogenital yang lembab sehingga menimbulkan iritasi yang menyebabkan
pengelupasan kulit. Akibat terjadinya pengelupasan kulit,maka sistem pertahanan
tubuh menurun dan akhirnya bakteri mudah masuk dan menginfeksi saluran
kemih bagian bawah terlebih dahulu, bakteri tersebut berkolonisasi pada
14
uretra,kemudian masuk ke dalam vesica urinaria , dan bermultiplikasi dan
menempel di vesica urinaria,sehingga timbul keluhan disuria, lalu bakteri menuju
ke ureter dan ginjal. Infeksi pada ginjal selanjutnya akan menimbulkan keluhan
demam tinggi.
4) Riwayat sejak bayi ibu penderita selalu memakaikan popok sekali pakai dan biasanya
diganti 2 kali pada siang hari dan hanya 1 kali pada malam hari.
a. Apa dampak dari riwayat pemakaian popok seperti pada kasus ?
Penyebab ruam popok yang paling utama adalah popok yang lembab. Popok
yang lama terkena air seni dan tinja bisa menimbulkan iritasi pada kulit. Bila
tidak segera membersihkannya, bakteri dan jamur akan tumbuh. Selain karena
lembab ada juga bayi yang memang alergi terhadap popok sekali pakai. Lebih
baik gunakan popok tradisional dengan resiko harus lebih sering
menggantinya bila bayi buang air kecil atau besar.
Peningkatan risiko ISK dapat terjadi oleh karena pemakaian popok sekali
pakai yang lama diganti yang menyebabkan daerah perineal menjadi lembab
sehingga menyebabkan munculnya bakteri uropatogenik. Bakteri dari saluran
kemih ini dapat naik ke ureter sampai ke ginjal, melalui suatu lapisan tipis
cairan (films of fluid), bertambah lagi bila ada refluks vesiko ureter dan
refluks intrarenal. Hal ini sering terjadi pada anak oleh karena kurangnya
kontraksi pada dasar pelvis sehingga setiap habis berkemih masih ada sisa
urin yang tertahan sehingga mengakibatkan refluks bakteri dari uretra ke
kandung kemih. Hal lain yang dapat menyebabkan munculnya bakteri tipe
uropatogenik adalah obstruksi urin, kelainan struktur, urolitiasis, benda asing,
refluks, dan lain-lain.
b. Bagaimana frekuensi ideal pergantian popok ?
Bayi berkemih sekurangnya 8 sampai 20 kali sehari tergantung dari usia dan
frekuensi pemberian makan atau minum. Bayi usia kurang dari 1 bulan
berkemih 20 kali dalam sehari. Popok sekali pakai dipromosikan sebagai
produk yang memiliki daya serap urin yang tinggi, bahkan dapat menampung
15
urin sebanyak ± 5 gelas ( 1 gelas = 60 ml ), sehingga dapat lebih lama diganti.
Rata-rata penggantian popok normal bisa berkisar antara 6-10 kali sampai 10-
12 kali tergantung usia dan daya serap popok.
5) Pada pemeriksaan fisik:
Anak tampak sakit berat, suhu 39,50 C, nadi 100x/menit, pernafasan 36 x/menit, TD 90/60
mmHg, BB = 10 kg, TB = 75 cm.
Pemeriksaan paru dan jantung dalam batas normal.
Pemeriksaan abdomen datar, lemas, hepar/lien tidak teraba, tidak teraba massa, bising
usus normal, nyeri ketok costovertebral dan nyeri tekan suprapubik sulit dinilai.
Regio anogenital: hiperemis dan ruam makulopapular di area yang ditutupi popok
a. Apa Interpretasi dari Pemeriksaan fisik?
Pemeriksaan Fisik Nilai Normal InterpretasiKeadaan Umum : Tampak sakit berat
Sehat Tidak Normal
Suhu 39,5 oC 36,5-37,2 oC FebrisNadi 100 x/menit 2-12 bulan <160/min NormalPernapasan 36 x/menit 2-12 bulan <50/menit NormalTD 90/60 mmHg 70-96/50-65 mmHg NormalBB=10 kg, TB= 75 cm 10 bulan BB: ±9,3kg TB: ±72
cmRange :+2 dan -2 standar deviasi dari nilai rata-rata
Normal
Pemeriksaan abdomen Datar, Lemas Hepar/lien tidak teraba Tidak teraba massa Bising usus normal Nyeri ketok cortovertebral dan nyeri tekan suprapubik sulit dinilai.
Datar, LemasTidak teraba/hati 1 jari teraba Massa tidak adaNormal : 3-5 x / menitTidak Nyeri
NormalNormalNormalNormalRagu
Regio anogenital :Hiperemis dan Ruam Makupopular di area yang ditutupi popok.
Tidak ada Tidak Normal. Kolonisasi bakteri usus dan iritasi kulit
16
b. Bagaimana mekanisme abnormalitas dari pemeriksaan fisik?
Mekanisme demam :
Demam adalah kenaikan suhu tubuh di atas normal. Dalam kasus ini, demam
terjadi sebagai pertanda telah terjadi infeksi. Zat yang dapat menyebabkan
demam disebut sebagai pirogen. Pirogen ada 2 jenis, yaitu pirogen endogen
dan pirogen eksogen. Pirogen endogen adalah zat yang berasal dari tubuh
hospes dan pirogen eksogen adalah zat yang berasal dari luar tubuh hospes.
Mayoritas pirogen eksogen adalah mikroorganisme itu sendiri yang
difagositosis, produk mereka atau toxin yang mereka hasilkan. Sebagai respon
terhadap rangsangan pirogen eksogen, maka monosit dan makrofag
mengeluarkan pirogen endogen IL-1(interleukin 1), TNFα (Tumor Necrosis
Factor α), IL-6 (interleukin 6), dan INFα (interferon α). (Isselbacher et al,
2012 : 98) Pirogen tersebut akan beredar dalam sistem vaskular.
Di hipothalamus anterior, terdapat suatu daerah yang kaya neuron yang
disuplai oleh suatu jaringan vaskular yang disebut sebagai organum
vasculorum laminae terminalis (OVLT). Sel – sel endotel di daerah ini akan
melepaskan metabolit asam arakhidonat ketika terpapar pirogen endogen.
Metabolit asam aradikonat, yang sebagian besar adalah Prostaglandin E2
yang dihasilkan melalui jalur COX-2 (cyclooxygenase 2), akan berdifusi ke
dalam hipothalamus. Pusat termoregulasi hipotalamus akan meningkatkan
patokan termostat suhu tubuh kita. Hipotalamus akan berusaha
mempertahankan suhu di titik termostat yang baru tersebut sehingga
hipotalamus merasa bahwa suhu normal tubuh kita (37° C) sebagai terlalu
dingin. Hipothalamus melalui sistem saraf eferen akan memerintahkan
pembuluh darah perifer untuk vasokontriksi sehingga terjadi konservasi panas.
Produksi panas tubuh juga akan ditingkatkan melalui mekanisme menggigil
(kontraksi otot dapat meningkatkan produksi panas). Konservasi panas dan
peningkatan produksi panas akan membuat suhu tubuh kita naik menuju set
point yang baru sehingga kita menjadi demam. (Isselbacher et al, 2012 : 98)
17
Mekanisme diaper rash :
Penggunaan popok yang tidak tepat lembab pada bagian anogenital
iritasi kulit anogenital hiperemis dan ruam
6) Hasil pemeriksaan laboratorium rutin:
Hematologi: Hb: 11 g/dl, lekosit: 23.000/mm3, Hitung jenis 0/1/4/80/13/2. LED
40mm/jam.
Urinalisis: warna kuning, agak keruh, lekosit penuh, eritrosit, 5-6/lpb, lekosit esterase
positif, nitrit positif.
a. Apa interpretasi dari Pemeriksaan Lab ?
Hasil Lab Nilai Normal InterpretasiHematologi
Hb: 11 g/dlLekosit: 23000/mm
Hitung jenis: 0/1/4/80/13/2
LED: 40 mm/jam
10-17 gram/dL5700-10000 sel/mm3
Basofil 0-1%Eosinofil 1-3%Netrofil batang 3-5%Netrofil segmen 50-70Limfosit 25-35%Monosit 2-8%
0-10 mm/jam
NormalLeukositosis
NormalNormalNormalMeningkatMenurunNormal
Meningkat
Urinalisis:
Warna kuningAgak keruhLekosit penuhEritrosit 5-6/lpbLekosit esterase (+)Nitrit (+)
Warna KuningTidak keruhTiada ada lekositNormalnya sedikitLekosit esterase (-)Nitrit (-)
NormalTidak normalPyuriaMeningkatTerjadi infeksiTerjadi infeksi
b. Bagaimana Mekanisme abnormal ?
- Leukosit esterase: pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat apakah ada
leukosit di dalam urin. Adanya leukosit di dalam urin akan memberikan
hasil positif, yang kemungkinan menandakan adanya ISK. Pemeriksaan
18
57-96% sensitif and 94-98% spesifik. Guna enzim ini pada leukosit adalah
disintegrasi esters menjadi alcohol dan asam.
- Nitrit (+): Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi produk dari enzim
nitrat reductase, sebuah enzim yang diproduksi oleh banyak bakteri.
- Leukosit penuh, eritrosit 5-6 Lpb: interpretasi dari hasil ini adalah adanya
infeksi ( namun pada kasus lain bisa juga menandakan adanya tumor, batu,
pembesaran prostate pada laki2, dan trauma)
- LED: Pada terjadinya inflamasi terjadi peningkatan sirkulasi dari
fibrinogen sehingga pada pemeriksaan LED sel darah merah lebih cepat
clumping dan mengendap.
7) Hasil pemeriksaan lanjutan:
Kultur urin: Proteus mirabilis >100.000/ul, sensitive dengan cotrimoxazole dan
cefotaxime (cara pengambilan dengan urin pancar tengah/mid stream)
USG TUG: pembengkakan parenkim ginjal serta batas kortikomedulla tidak jelas
a. Apa interpretasi dari Pemeriksaan lanjutan ?
Hasil Pemeriksaan Lanjutan Normal InterpretasiKultur Urin:Proteus Mirabilis >100000/ul, sensitive dengan cotrimoxazole dan cefotaxime
Tidak ada Terjadi infeksi
USG TUG: pembengkakan parenkim ginjal serta batas kotikomedulla tidak jelas.
Tidak ada pembengkakan Terjadi infeksi
b. Bagaimana mekanisme abnormal pada pemeriksaan lanjutan ?
Mekanisme kultur urine ditemukan proteus mirabilis . 100.000/mlPemakaian popok sekali pakai yang lama diganti yang menyebabkan daerah
perineal menjadi lembab sehingga menyebabkan munculnya bakteri
uropatogenik. Bakteri dari saluran kemih ini dapat naik ke ureter sampai ke
ginjal, melalui suatu lapisan tipis cairan (films of fluid), bertambah lagi bila
ada refluks vesiko ureter dan refluks intrarenal. Hal ini sering terjadi pada
anak oleh karena kurangnya kontraksi pada dasar pelvis sehingga setiap habis
19
berkemih masih ada sisa urin yang tertahan sehingga mengakibatkan refluks
bakteri dari uretra ke kandung kemih. Sehingga pada kultur urin didapat
Proteus mirabilis.
Mekanisme pembengkakan parenkim ginjal serta batas kortikomedulla tidak jelasProteus mirabilis dari anal ke urethra Refluks vesikouretra Ureter ke
pelvis renalis Refluks intrarenal Infeksi pada parenkim ginjal
Akumulasi leukosit dan mediator radang Inflamasi pembengkakan
parenkim ginjal batas kortikomedulla tidak jelas.
c. Bagaimana farmakokinetik dan farmakodinamik dari cotrimoxazole ?
FARMAKODINAMIK
Trimetoprim,suatu trimetoksibenzilpirimidin,secara selektif menghambat
asam dihidrofolat reduktase bakteri, yang mengubah asam dihidrofolat
menjadi asam tetrahidrofolat,suatu tahap menuju sintesis purin dan pada
akhirnya sintesis DNA. Trimetoprim kira-kira 50.000 kali lebih tidak efisien
dalam menghambat asam dihidrofolat reduktase pada sel mamalia .
Pirimetamin,suatu benzilpirimidin lain,secara selektif menghambat asam
dihidrofolat reduktase pada protozoa dibandingkan sel mamalia. Sulfonamid
menghambat masuknya molekul PABA (para-aminobenzoic acid) ke dalam
molekul asam folat. Trimetoprim atau pirimetamin dalam kombinasi dengan
sulfonamida menyekat tahapan sekuensial dalam sintesis folat dan
menghasilkan peningkatan bermakna (sinergisme) aktivitas kedua obat.
Kombinasi ini seringkali bersifat bakterisidal,dibandingkan dengan aktivitas
bakteriostatis sulfonamida saja.
Resistensi bakteri frekuensi terjadinya resistensi terhadap kotrimoksazol lebih
rendah dari pada terhadap masing-masing obat karena mikroba yang resisten
teradap salah satu komponen masih peka terhadap komponen yang lainnya.
FARMAKOKINETIK
20
Trimetoprim biasanya diberikan peroral, sendiri atau dalam kombinasi dengan
sulfametoksazol,keduanya mempunyai waktu paruh yang serupa.
Trimetoprim-sulfametoksazol juga dapat diberikan secara intravena.
Trimetoprim diserap dengan baik dari usus dan didistribusikan secara luas
dalam cairan dan jaringan tubuh, termasuk cairan cerebrospinal. Karena
trimetoprim lebih larut dalam lipid daripada sulfametoksazol,trimetoprim
memiliki volume distribusi yang lebih besar ketimbang sulfametoksazol. Oleh
sebab itu,ketika 1 bagian trimetoprim diberikan dengan 5 bagian
sulfametoksazol ( rasio formulasi), kadar puncak dalam plasmanya berada
dalam rasio 1:20,yang optimal bagi efek gabungan kedua obat ini in
vitro.Sekitar 30-50% sulfonamida dan 50-60% trimetoprim ( atau masing-
masing metabolitnya diekskresi di urine dalam waktu 24 jam.
d. Bagaimana farmakokinetik dan farmakodinamik dari cefotaxime ?
FARMAKODINAMIK
Cefotaxime adalah antibiotik sefalosporin generasi ketiga yang memiliki
aktivitas anti bakteri. Aktivitas bakterisidal didapat dengan cara menghambat
sisntesis dinding sel. In vitro cefotaxime memiliki aktivitas luas terhadap
bakteri gram positif dan gram negatif. Cefotaxime memiliki stabilitas yang
sangat tinggi terhadap β-laktamase, baik itu penisilinase dan sefalosporinase
yang dihasilkan bakteri gram-positif dan gram-negatif. Selain daripadaitu
Cefataxime merupakan penghambat poten terhadap bakteri gram negatif
tertentu yang menghasilkan β-laktamase.
FARMAKOKINETIK
1.Absorpsi: Cefotaxime diberikan secara injeksi sebagai garam natrium.
Diabsorpsi dengan cepat setelah injeksi intra muskular dengan rata-rata
konsentrasi puncak plasma sekitar 12 dan 20 ug/ml yang dilaporkan berturut-
urut setelah 40 menit pemberian Cefotaxime 0,5 dan 1 g. pada injeksi
intravena Cefotaxime 0,5:1 atau 2 g rata-rata konsentrasi puncak plasma
berturut-urut 38:102 dan 215 ug/ml dicapai dalam konsentrasi bervariasi
21
antara 1 sampai 3 ug/ml setelah 4 jam. Waktu paruh plasma Cefotaxime
sekitar 1 jam dan untuk metabolit aktif desocetylcepotaxime sekitar 1,5 jam.
Waktu paruh meningkat pada neonatus dan penderita dengan gangguan ginjal
berat, terutama untuk bentuk metabolit, dalam hal ini pengurangan dosis
sangat diperlukan. Sekitar 40% Cefotaxime dalam sirkulasi dilaporkan
berikatan dengan protein plasma.
2.Distribusi: Cefotaxime dan desacetylcefotoxime secara luas didistribusikan
dalam jaringan dan cairan tubuh; konsentrasi terapi dapat ditemui dalam LCS
terutama bila meninges dalam keadaan meradang. Cefotaxime melewati
plasenta dan dalam konsentrasi rendah dapat ditemukan pada air susu ibu.
Konsentrasi Cefotaxime dan desacetylcefotaxime relatif tinngi pada empedu
dan 20% dari dosis yang diberikan ditemukan dalam feses.
3.Metabolisme: Cefotaxime sebagian masuk dalam metabolisme hati menjadi
desacetylcefotaxime dan metabolit inaktif.
4.Ekskresi: Eliminasi Cefotaxime terutama melalui ginjal dan sekitar 40
sampai 60% dari dosis ditemukan tidak berubah di urin dalam jangka waktu
24 jam; dan sisanya sebanyak 20% diekskresikan sebagai metabolit desacetyl.
Probenesid akan berkompetensi dengan Cefotaxime dalam halsekresi melalui
tubulus ginjal yang akan mengakibatkan konsentrasi plasma efotaxime dan
metabolit desacetyl menjadi lebih tinggi dan lebih lama. Cefotaxime dan
metabolitnya dapat dihilangkan dengan hemodialis.
8) Apa differential diagnosis pada kasus ini ?
- Urethritis irritan
-Vaginitis
-Appendisitis
-Endometriosis
-Nephrolitisasis
22
Jika ditemukan batuk, pilek, atau diare maka kemungkan ISPA yang paling mungkin
belum dapat di sisngkirkan
9) Bagaimana cara menegakkan diagnosis pada kasus ini ?
1. Anamnesis
Anamnesis harus dilakukan secara menyeluruh. Keluhan nyeri harus benar-benar
ditelusuri untuk mengetahui nyeri apa yang dirasakan oleh pasien yang dapat
digunakan oleh dokter untuk menegakkan diagnosis.
Onset keluhan nyeri berapa lama?
Karakteristik nyerinya seperti apa?
Penyebaran nyeri?
Aktivitas yang dapat membuat bertambahnya nyeri ataupun berkurangnya nyeri?
Apakah ada riwayat muntah?
Apakah ada gross hematuria?
Apakah ada riwayat nyeri yang sama sebelumnya?
Apakah ada demam?
2. Pemeriksaan fisik
Pemeriksaan fisik yang dilakukan, yaitu pemeriksaan tanda vital dan pemeriksaan fisik
khusus. Pemeriksaan tanda vital yang dinilai, yaitu tekanan darah, frekuensi pernapasan
dan nadi, serta suhu tubuh. Pada pemeriksaan fisik khusus, dilakukan 4 tahap
pemeriksaan yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi.
Keadaan umum anak tampak sakit berat.
Suhu tubuh 39,5°C: menandakan anak menderita demam. Demam merupakan
gejala yang umum, tetapi infeksi kandung kemih (sistitis) biasanya tidak menyebabkan
demam. Suatu infeksi bakteri pada ginjal (pielonefritis) biasanya menyebabkan demam
tinggi. Kanker ginjal kadang menyebabkan demam.
Tidak ada kelainan jantung, paru, maupun abdomen.
3. Pemeriksaan Penunjang
Pemeriksaan laboratorium
23
Anamesis dan pemeriksaan fisik mengarah pada adanya kelainan pada sistem urinarius
anak. Maka pemeriksaan lab yang dibutuhkan antara lain
Pemeriksaan darah
Kadar Hb
Protein
Hasil lab menyatakan
bahwa anak menderita
proteinuria
ringan (protein +).
Proteinuria
biasanya merupakan
pertanda dari suatu
penyakit ginjal, tetapi bisa
juga terjadi secara
normal setelah olah raga
berat (misalnya
maraton). Proteinuria juga bisa terjadi pada proteinuria ortostatik, dimana protein baru
muncul di dalam urin setelah penderitanya berdiri cukup lama, dan tidak akan
ditemukan di dalam urin setelah penderitanya berbaring.
Glukosa
Hasil lab urin tidak mengandung glukosa.
Leukosit
Dilaporkan jumlah leukosit 15-20/LPB. Piuria dapat ditemukan pada pielonefritis,
sistitis, prostatitis, juga uretritis.
Eritrosit
Pada urin ditemukan 8-12 eritrosit per LPB. Hematuria dapat ditemukan pada banayak
keadaan antara lain kelainan membrane glomerulus, trauma vascular ginjal,
glomerulonefritis akut, infeksi akut ginjal, keganasan.
Silinder
Merupakan cetakan protein yang terjadi dalam tubuli ginjal. Pada hasil lab tidak
didapati adanya silinder, menandakan tidak adanya kelainan pada tubuli ginjal.
24
Usia Kadar normal Hb
Bayi baru lahir 17-22 gram/dl
Umur 1 minggu : 15-20 gram/dl
Umur 1 bulan : 11-15 gram/dl
Anak anak 11-13 gram/dl
Perempuan dewasa 14-18 gram/dl
Lelaki dewasa 12-16 gram/dl
Lelaki tua 12.4-14.9 gram/dl
Perempuan tua 11.7-13.8 gram/dl
Leukosit esterase(enzim yang ditemukan pada sel darah putih tertentu)
Hasil positif di dalam urin merupakan pertanda adanya peradangan, yang paling sering
disebabkan oleh infeksi bakteri. Pemeriksaan ini mungkin merupakan negatif palsu jika
urin sangat pekat atau mengandung gula, garam empedu, obat-obatan (misalnya
rifampcin,vitaminC)
10) Apa working diagnosis pada kasus ini ?
Anisa, 10 bulan, dengan keluhan utama panas tinggi sejak 2 hari yang lalu menderita
Pyelonefritis akut dengan faktor predisposisi ruam popok akibat penggunaan popok yang
tidak tepat.
11) Apa Patogenesis pada kasus ini ?
Pada bayi dan anak anak biasanya bakteri berasal dari tinjanya sendiri ataupun
dikarenakan jarak antara uretra dan peri anal yang pendek sehingga dapat menjalar
secara asending. Bakteri uropatogenik yang melekat pada pada sel uroepitelial, dapat
mempengaruhi kontraktilitas otot polos dinding ureter, dan menyebabkan gangguan
peristaltik ureter. Melekatnya bakteri ke sel uroepitelial, dapat meningkatkan virulensi
bakteri tersebut. Mukosa kandung kemih dilapisi oleh glycoprotein mucin layer yang
berfungsi sebagai anti bakteri. Robeknya lapisan ini dapat menyebabkan bakteri dapat
melekat, membentuk koloni pada permukaan mukosa, masuk menembus epitel dan
selanjutnya terjadi peradangan. Bakteri dari kandung kemih dapat naik ke ureter dan
sampai ke ginjal melalui lapisan tipis cairan (films of fluid), apalagi bila ada refluks
vesikoureter maupun refluks intrarenal. Bila hanya vesica urinaria yang terinfeksi, dapat
mengakibatkan iritasi dan spasme otot polos vesika urinaria, akibatnya rasa ingin miksi
terus menerus (urgency) atau miksi berulang kali (frequency), sakit waktu miksi (dysuri).
Mukosa vesika urinaria menjadi edema, meradang dan perdarahan (hematuria).
Infeksi ginjal dapat terjadi melalui collecting system. Pelvis dan medula ginjal dapat
rusak, baik akibat infeksi maupun oleh tekanan urin akibat refluks berupa atrofi ginjal.
Kandung kemih awalnya diinokulasi dengan organisme menular, yang kemudian
bermigrasi ke atas. Infeksi ascending ini terjadi karena sifat virulensi khusus dari bakteri,
seperti adhesin P fimbriae dan endotoksin. Endotoksin diyakini menghambat peristaltik
25
saluran kemih dengan cara memblokir saraf-adrenergik dalam otot polos, sehingga
menciptakan fungsional obstruksi. Obstruksi fungsional ini dapat menyebabkan aliran
maju urin yg merupakan proteksi normal terhadap infeksi jadi terhambat sehingga
kuman dapat naik keatas (ascending).
Pada pielonefritis akut dapat ditemukan fokus infeksi dalam parenkim ginjal, ginjal
dapat membengkak, infiltrasi lekosit polimorfonuklear dalam jaringan interstitial,
akibatnya fungsi ginjal dapat terganggu. Pada pielonefritis kronik akibat infeksi, adanya
produk bakteri atau zat mediator toksik yang dihasilkan oleh sel yang rusak,
mengakibatkan parut ginjal (renal scarring).
12) Apa pemeriksaan penunjang pada kasus ini ?
Urinalisis
Komponen urinalisis yang paling penting dalam ISK adalah esterase leukosit, nitrit, dan
pemeriksaan leukosit dan bakteri mikroskopik. Namun tidak ada komponen urinalisis
yang dapat menggantikan pentingnya kultur sehingga kultur tetap merupakan keharusan
untuk mendiagnosis ISK
Kultur urin
26
Urinalysis Interpretasi Sensitivitas Spesifisitas
Leukosit > 3/lpb 32-100% 45-97%
Leukosit
esterase (LE)
test
Positif 67-94% Lower
Nitrit test Positif
Bacteriuria Positif
Metode pengambilan
sampel urin
Cutoff level colony forming
unit (CFU/ml)
Urin pancar tengah 100.000
Kateterisasi 50.000
Aspirasi supra pubik Berapapun
Kultur (kultur : pembiakan mikroorganisme) yang negatif akan menyingkirkan diagnosis
ISK. Sedangkan pada kultur yang positif, proses pengambilan contoh urin harus
diperhatikan. Jika kultur positif berasal dari aspirasi suprapubik atau kateterisasi, maka
hasil tersebut dianggap benar. Namun jika kultur positif diperoleh dari kantung
penampung urin, perlu dilakukan konfirmasi dengan kateterisasi atau aspirasi suprapubik.
Ultrasonografi ginjal
Pemeriksaan ini dilakukan pada semua anak dengan ISK sesegera mungkin. USG
berguna untuk menentukan ukuran dan bentuk ginjal,struktur dan kelainan anatomis,
tetapi tidak dapat digunakan untuk mendeteksi vesicoureteral reflux (VUR) dan scar pada
ginjal. Pada pielonefritis ditemukan pembengkakan parenkim ginjal,batas kortikomedula
yang tidak jelas. Kerugian USG adalah tidak dapat memberikan informasi mengenai
fungsi ginjal.
VCUG dan Nuclear cystography
Voiding cystourethrography (VCUG) dan nuclear cystography berguna untuk
memvisualisasikan anatomi uretra dan kandung kemih dan dapat mendeteksi
Vesicoureteral reflux (VUR)
DMSA scan
Pemeriksaan ini terutama untuk melihat fungsi saluran kemih. DMSA biasanya dilakukan
pada anak di bawah 5 tahun dengan hasil ultrasonografi yang tidak normal. Umumnya
dilakukan 2 bulan setelah episode ISK untuk memberi waktu perbaikan pada saluran
kemih. Selama menunggu dilakukannya pemeriksaan ini, beberapa pihak menganjurkan
pemberian antibiotik dosis rendah. Scan ini digunakan untuk memeriksa struktur ginjal,
ukuran dan bentuk. Hal ini sangat umum digunakan pada anak-anak yang memiliki
infeksi saluran kemih. DMSA scan Ini dapat menunjukkan daerah ginjal yang bekerja
dengan baik dan scar pada ginjal . Scar tersebut dapat disebabkan oleh kondisi yang
disebut refluks vesiko-ureter . DMSA scan juga dapat mengetahui kerusakan setelah
cedera atau berkurangnya pasokan darah ke ginjal.
27
Penanda inflamasi (CRP dan Procalcitonin)
Jumlah WBC yang tinggi tidak spesifik dan tidak membantu dalam membedakan ISK
bawah dan ISK bagian atas. Konsentrasi CRP sensitif, tetapi tidak spesifik untuk
menandakan keterlibatan parenkim ginjal pada bayi yang demam dan anak dengan ISK.
Nilai CRP dapat digunakan untuk membedakan kolonisasi kandung kemih dari
pielonefritis akut pada anak demam dengan bakteriuria dan neurogenik bladder.
Procalcitonin merupakan penanda inflamasi akut dengan sensitivitas 70-95% dan
spesifisitas yang mendekati 90% untuk keterlibatan ginjal pada bayi dan anak dengan
ISK demam. Meskipun kurang sensitif dibandingkan CRP, prokalsitonin lebih spesifik
untuk diagnosis pielonefritis akut. Karena tingkat procalcitonin meningkat, tingkat
keparahan lesi ginjal pada DMSA meningkat. Tingginya tingkat procalcitonin
memprediksi VUR pada bayi dan anak-anak pada awal pielonefritis
13) Apa faktor resiko pada kasus ini ?
-Wanita memiliki risiko besar mengalami infeksi ginjal dari pada laki-laki. Ini
dikarenakan wanita memiliki uretra lebih pendek daripada laki-laki sehingga bakteri
mudah mencapai ginjal.
-Personal hygiene yang kurang
-System imun yang lemah
-Kurang minum
-Sering menahan BAK
-Kerusakan syaraf disekitar kandung kemih.
-Penggunaan kateter dalam jangka waktu lama
14) Apa penatalaksaan pada kasus ini ?
Prinsip pengobatan infeksi saluran kemih adalah memberantas (eradikasi) bakteri dengan
antibiotika.
Tujuan pengobatan :
Menghilangkan bakteri penyebab Infeksi saluran kemih.
28
Menanggulangi keluhan (gejala).
Mencegah kemungkinan gangguan organ ( terutama ginjal).
Tata cara pengobatan :
Menggunakan pengobatan dosis tunggal.
Menggunakan pengobatan jangka pendek antara 10-14 hari.
Menggunakan pengobatan jangka panjang antara 4-6 minggu.
Menggunakan pengobatan pencegaham (profilaksis) dosis rendah.
Menggunakan pengobatan supresif, yaitupengobatan lanjutan jika pemberantasan
(eradikasi) bakteri belum memberikan hasil.
Pengobatan infeksi saluran kemih menggunakan antibiotika yang telah diseleksi terutama
didasarkan pada beratnya gejala penyakit, lokasi infeksi, serta timbulnya komplikasi.
Pertimbangan pemilihan antibiotika yang lain termasuk efek samping, harga, serta perbandingan
dengan terapi lain. Tetapi, idealnya pemilihan antibiotika berdasarkan toleransi dan terabsorbsi
dengan baik, perolehan konsentrasi yang tinggi dalam urin, serta spectrum yang spesifik terhadap
mikroba pathogen.
Pengobatan yang pertama dilakukan ke symptom nya seperti pada kasus ini sakit kencing dapat
digunakan fenazopiridin pyiridium dengan dosis 7-10 mg/kgbb/hari. Selain itu cari tau factor
predisposisi nya pada kasus ini alergi akibat infeksi yang bisa digunakan. Pada infeksi akut yang
simpleks diberikan (primary drug) ialah ampisilin kontrisokmazol,sulfisoksazol,
nitrofurantoin.pemakaian nya selama 7 hari.
Selain itu, Antibiotika yang digunakan untuk pengobatan infeksi saluran kemih terbagi
dua, yaitu antibiotika oral dan parenteral.
I. Antibiotika Oral
a. Sulfonamida
Antibiotika ini digunakan untuk mengobati infeksi pertama kali. Sulfonamida
umumnya diganti dengan antibiotika yang lebih aktif karena sifat resistensinya.
Keuntungan dari sulfonamide adalah obat ini harganya murah.
b. Trimetoprim-sulfametoksazol
29
Kombinasi dari obat ini memiliki efektivitas tinggi dalam melawan bakteri aerob,
kecuali Pseudomonas aeruginosa. Obat ini penting untuk mengobati infeksi dengan
komplikasi, juga efektif sebagai profilaksis pada infeksi berulang. Dosis obat ini adalah
160 mg dan interval pemberiannya tiap 12 jam.
c. Penicillin
Ampicillin adalah penicillin standar yang memiliki aktivitas spektrum luas,
termasuk terhadap bakteri penyebab infeksi saluran urin. Dosis ampicillin 1000
mg dan interval pemberiannya tiap 6 jam.
Amoxsicillin terabsorbsi lebih baik, tetapi memiliki sedikit efek samping.
Amoxsicillin dikombinasikan dengan clavulanat lebih disukai untuk mengatasi
masalah resistensi bakteri. Dosis amoxsicillin 500 mg dan interval pemberiannya
tiap 8 jam.
d. Cephaloporin
Cephalosporin tidak memiliki keuntungan utama dibanding dengan antibiotika
lain yang digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih, selain itu obat ini juga lebih
mahal. Cephalosporin umumnya digunakan pada kasus resisten terhadap amoxsicillin dan
trimetoprim-sulfametoksazol.
e. Tetrasiklin
Antibiotika ini efektif untuk mengobati infeksi saluran kemih tahap awal. Sifat
resistensi tetap ada dan penggunannya perlu dipantau dengan tes sensitivitas. Antibotika
ini umumnya digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh chlamydial.
f. Quinolon
Asam nalidixic, asam oxalinic, dan cinoxacin efektif digunakan untuk mengobati
infeksi tahap awal yang disebabkan oleh bakteri E. coli dan Enterobacteriaceae lain,
tetapi tidak terhadap Pseudomonas aeruginosa. Ciprofloxacin ddan ofloxacin
diindikasikan untuk terapi sistemik. Dosis untuk ciprofloxacin sebesar 50 mg dan interval
pemberiannya tiap 12 jam. Dosis ofloxacin sebesar 200-300 mg dan interval
pemberiannya tiap 12 jam.
g. Nitrofurantoin
30
Antibiotika ini efektif sebagai agen terapi dan profilaksis pada pasien infeksi
saluran kemih berulang. Keuntungan utamanya adalah hilangnya resistensi walaupun
dalam terapi jangka panjang.
h. Azithromycin
Berguna pada terapi dosis tunggal yang disebabkan oleh infeksi chlamydial.
i. Methanamin Hippurat dan Methanamin Mandalat
Antibiotika ini digunakan untuk terapi profilaksis dan supresif diantara tahap
infeksi.
II. Antibiotika Parenteral.
a. Amynoglycosida
Gentamicin dan Tobramicin mempunyai efektivitas yang sama, tetapi gentamicin
sedikit lebih mahal. Tobramicin mempunyai aktivitas lebih besar terhadap pseudomonas
memilki peranan penting dalam pengobatan onfeksi sistemik yang serius. Amikasin
umumnya digunakan untuk bakteri yang multiresisten. Dosis gentamicin sebesar 3-5
mg/kg berat badan dengan interval pemberian tiap 24 jam dan 1 mg/kg berat badan
dengan interval pemberian tiap 8 jam.
b. Penicillin
Penicillin memilki spectrum luas dan lebih efektif untuk menobati infeksi akibat
Pseudomonas aeruginosa dan enterococci. Penicillin sering digunakan pada pasien yang
ginjalnya tidak sepasang atau ketika penggunaan amynoglycosida harus dihindari.
c. Cephalosporin
Cephalosporin generasi kedua dan ketiga memiliki aktivitas melawan bakteri
gram negative, tetapi tidak efektif melawan Pseudomonas aeruginosa. Cephalosporin
digunakan untuk mengobati infeksi nosokomial dan uropsesis karena infeksi pathogen.
d. Imipenem/silastatin
Obat ini memiliki spectrum yang sangat luas terhadap bakteri gram positif,
negative, dan bakteri anaerob. Obat ini aktif melawan infeksi yang disebabkan
enterococci dan Pseudomonas aeruginosa, tetapi banyak dihubungkan dengan infeksi
31
lanjutan kandida. Dosis obat ini sebesar 250-500 mg ddengan interval pemberian tiap 6-8
jam.
e. Aztreonam
Obat ini aktif melawan bakteri gram negative, termasuk Pseudomonas
aeruginosa. Umumnya digunakan pada infeksi nosokomial, ketika aminoglikosida
dihindari, serta pada pasien yang sensitive terhadap penicillin. Dosis aztreonam sebesar
1000 mg dengan interval pemberian tiap 8-12 jam.
15) Apa komplikasi pada kasus ini ?
a. Nekrosis papila ginjal. Sebagai hasil dari proses radang, pasokan darah pada area
medula akan terganggu dan akan diikuti nekrosis papila guinjal, terutama pada penderita
diabetes melitus atau pada tempat terjadinya obstruksi.
b. Fionefrosis. Terjadi apabila ditemukan obstruksi total pada ureter yang dekat sekali
dengan ginjal. Cairan yang terlindung dalam pelvis dan sistem kaliks mengalami
supurasi, sehingga ginjal mengalami peregangan akibat adanya pus.
c. Abses perinefrik. Pada waktu infeksi mencapai kapsula ginjal, dan meluas ke
dalam jaringan perirenal, terjadi abses perinefrik.
16) Apa pencegahan pada kasus ini ?
Berikut merupakan pencegahannya, seperti :
1. Ganti popok sesering mungkin. Bila si kecil buang air besar, jangan menunda-
nunda untuk segera menggantinya.
2. Minimalisasikan penggunaan tissue basah untuk membersihkan area popoknya. Air
bersih adalah pilihan terbaik.
3. Hindari menggesek kulit bayi walau pun dengan handuk lembut. Sebaiknya tepuk-
tepuk dan angin-anginkan saja pantat si kecil untuk mengeringkannya.
4. Beri sirkulasi udara untuk area kulitnya yang terkena popok dengan cara
menggunakan popok kain, khususnya pada waktu tidur.
5. Jangan mengikat atau merekatkan popok terlalu kencang.
6. Bila ruam tidak hilang lebih dari 3 hari konsultasikan segera ke dokter, terutama
bila timbul demam dan tidak nafsu makan.
32
7. Jangan mengolesi ruam (bintik-bintik merah) dengan lotion atau baby oil. Gunakan
salep anti jamur yang mengandung Zinc di bawah pengawasan dokter.
17) Apa prognosis pada kasus ini ?
Prognosis tergantung ada tidaknya kelainan anatomi,usia dan kecepatan serta ketepatan terapi. Sebagian besar kasus pielonefritis memiliki respon cepat terhadap pengobatan antibiotik tanpa gejala sisa lebih lanjut. Scar ginjal permanen dapat terjadi pada 18-24% anak-anak setelah pielonefritis akut. Pengobatan dalam waktu 5-7 hari dari awal secara signifikan mengurangi pembentukan scar ginjal. Untuk pasien dengan kasus yang parah atau infeksi kronis, perawatan yang tepat, pencitraan, dan tindak lanjut membantu untuk mencegah gejala sisa jangka panjang. Vesico-ureteral reflux (VUR) sering sembuh tanpa kerusakan permanen.
18) Apa KDU pada kasus ini ?
Tingkat IV
Mampu membuat diagnosis klinik berdasar pemeriksaan fisik dan pemeriksaan
tambahan. Dapat memutuskan dan mampu menangani problem itu secara mandiri hingga
tuntas.
IV. Kerangka Konsep
33
Faktor predisposisi Faktor resiko
Penggunaan diapers yg kurang tepat
Iritasi VU terinfeksi
Usia, Uretra dan perianal pendek
Bakteri uropatogenik melekat pada sel uroepital
V. Kesimpulan
Anisa, 10 bulan, dengan keluhan utama panas tinggi sejak 2 hari yang lalu menderita
Pyelonefritis akut dengan faktor predisposisi ruam popok akibat penggunaan popok
yang tidak tepat.
VI. Learning Issues dan keterbatasan pengetahuan
34
Daya tahan kulit
Pengelupasan kulit
Kuman mudah masuk & berkembang
Respon peradangan pada dermis
Kerusakan membran lemak keratinosit
Hiperemis dan ruam makulopapular
Mengaktifkan fosfolipase
Pelepasan AA, DAG, IP3, inaktivasi platelet, histamin
Leukosit penuh LED
Urin agak keruh
ISK
Leukosit
esterase
virulensi bakteri
Disuria
Iritasi dan spasme otot polos VU
Infeksi ascending
Nitrit +
Reflux vesikoureter dan intrarenal
Fungsional obstruksi
Menghambat peristaltik saluran kemih
Memblokir saraf adrenergik dlm otot
Adhesin P fimbriae enditoxin
Demam
Pembesaran ginjal
Monosit dan makrofag mengeluarkan IL-1, IL-6, TNFα, INFα
Batas kortikomedula tidak jelas
Berkolonisasi di uretra
Proteus mirabilis 10⁵
Pokok Bahasan What I Know What I don’t
know
What I have to prove How I will
learn
Anatomi dan
fisiologi traktus
urinarius
Definisi Anatomi dan
fisiologi traktus
urinarius
Penjelasan lebih jelas
mengenai anatomi dan
fisiologi traktus
urinarius
Text book,
Jurnal, dan
Internet
Infeksi Saluran
kemih
Definisi Etiologi,
mekanisme,
diagnosis dan tata
laksana
Penjelasan lebih jelas
dan hubungan dengan
penyakit sekarang
Text book,
Jurnal, dan
Internet
Proteus
mirabilis
Definisi Keterkaitannya
dengan kasus
Penjelasan lebih jelas
mengenai Proteus
mirabilis
Text book,
Jurnal, dan
Internet
BAB III
SINTESIS
Anatomi dan fisiologi traktus urinarius
35
Sistem kemih (urinaria) terdiri dari organ-organ yang memproduksi urin dan menyalurkannya
keluar tubuh. Komponen dari sistem kemih terdiri dari:
a. Ginjal
Ginjal merupakan sepasang organ yang
berbentuk seperti kacang, berwarna merah
tua, terletak di belakang rongga abdomen.
Satu berada di setiap sisi kolumna
vertebralis dekat dengan garis pinggang dan
dua pasang iga terakhir. Ginjal dipasok oleh
arteri renalis dan vena renalis. Ginjal kanan
terletak agak di bawah dibanding dengan
ginjal kiri. Hal ini karena pada sisi kanan
terdapat hati. Panjang ginjal sekitar 12,5 cm dan tebal 2,5 cm. Ginjal laki-laki memiliki
berat sekitar 125-175 gr dan pada perempuan sekitar 115-155 g.
Fungsi spesifik dari ginjal meliputi:
- Mempertahankan keseimbangan H2O dalam tubuh
- Mengatur jumlah dan konsentrasi sebagian ion-ion penting
- Memelihara volume plasma yang sesuai
- Membantu memelihara keseimbangan asam-basa tubuh
- Memelihara osmolaritas darah
- Mengekskresikan produk-produk sisa dari metabolisme tubuh
- Mengekskresikan banyak senyawa asing
- Mensekresikan eritropoietin
- Mensekresikan renin
- Mengubah vitamin D dalam bentuk aktifnya.
Struktur internal sebuah ginjal berupa:
Hilum, yaitu tingkat kecekungan tepi medial ginjal
Sinus ginjal, yaitu rongga berisi lemak yang terbuka pada hilus. Tempat
menempelnya jalan keluar masuk ureter, vena dan arteri renalis, limfatik dan saraf.
36
Pelvis ginjal, yaitu perluasan ujung proksimal ureter, merupakan rongga pengumpul
sentral.
Parenkim ginjal, yaitu jaringan ginjal yang menutupi struktur sinus ginjal. Terbagi
menjadi medula dan korteks luar.
Medula terdiri dari massa triangular yang disebut piramida ginjal dan ujungnya yang
sempit disebut papila.
Korteks tersusun dari tubulus dan pembuluh darah nefron. Terletak di dalam antara
piramida medula yang bersebelahan untuk membentuk kolumna ginjal.
Lobus ginjal, yaitu bagian ginjal yang terdiri dari satu piramida ginjal, kolumna yang
saling berdekatan, dan jaringan korteks yang menyelubunginya.
b. Ureter
Ureter adalah sebuah duktus
berdinding otot polos yang keluar dari batas medial dekat pangkal arteri dan vena renalis.
37
Terdapat dua buah ureter yang mengalirkan urin dari masing-masing ginjal ke kandung
kemih.
c. Kandung Kemih
Kandung kemih (vesika urinaria) yaitu suatu kantung rongga yang berfungsi menyimpan
urin secara temporer. Dapat direnggangkan dan volumenya disesuaikan kontraktil otot
polosnya.
d. Uretra
Secara berkala, kandung kemih dikosongkan. Urin dikeluarkan keluar tubuh melalui
uretra. Uretra wanita berbentuk pendek dan lurus langsung dari leher kandung kemih
keluar tubuh. Uretra pria jauh lebih panjang dan melengkung melewati kelenjar prostat
dan penis. Uretra pria mempunyai dua fungsi, yaitu sebagi saluran untuk mengeluarkan
urin dan saluran untuk semen.
Selain beberapa komponen di atas, ada pula satuan fungsional ginjal yang juga sangat
berpengaruh dalam sistem kemih, yaitu nefron. Satu ginjal bisa terdapat 1-4 juta nefron
yang disatukan oleh jaringan ikat. Nefron mempunyai satu komponen vaskular dan satu
komponen tubular, terletak di dalam ginjal memebentuk dua daerah khusus. Daerah
sebelah luar tampak granuler yaitu di korteks ginjal dan daerah dalam yang berupa
segitiga-segitiga bergaris yaitu di piramida ginjal. Secara kolektif semua itu sebagai
medula. Nefron merupakan unit terkecil pembentuk urin. Karena fungsi utama dari ginjal
sendiri adalah memproduksi urin. Struktur nefron terdiri dari:
Glomerulus
Bagian dominan pada komponen vaskuler. Glomerulus adalah berkas kapiler
berbentuk bola tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dalam darah yang
melewatinya.
Kapsul Bowman
Komponen tubulus berawal dari kapsul bowman. Kapsul bowman adalah suatu
invaginasi berdinding rangkap yang melingkupi glomerulus. Kapsul bowman dan
glomerulus bersama-sama membentuk korpuskel ginjal.
Tubulus Kontortus Proksimal
Tubulus ini keseluruhan terletak di dalam korteks, panjangnya mencapai 15 mm.
Lengkung Henle (Ansa Henle)
38
Tubulus kontortus proksimal yang mengarah masuk ke dalam medula membentuk
lengkungan jepit dan membalik ke atas ke dalam korteks. Lengkungan yang
terbenam dalam medula disebut pars desendens dan yang berjalan kembali ke
korteks disebut pars asendens.
Tubulus Kontortus Distal
Berbentuk panjang dan berliku. Panjangnya mencapai 5 mm dan membentuk
segmen terakhir nefron
Tubulus dan Duktus Pengumpul
Setiap tubulus pengumpul berdesenden di korteks. Tubulus tersebut akan
mengalir ke sejumlah tubulus kontortus distal. Tubulus pengumpul membentuk
duktus pengumpul besar yang lurus. Duktus pengumpul membentuk tuba yang
lebih besar ke dalam ginjal melalui kaliks minor. Kaliks minor bermuara ke pelvis
ginjal melalui kaliks mayor. Dari pelvis ginjal, urin dialirkan melalui ureter
menuju kandung kemih.
39
Mengingat kembali fungsi primer ginjal merupakan penghasil urin dan mengekskresi zat sisa
metabolisme tubuh, terdapat tiga proses utama pembentukan urin. Ketiga proses tersebut adalah
filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan sekresi tubulus.
A. Filtrasi Glomerulus
Adalah perpindahan (filtrasi) cairan dan zat terlarut dari kapiler glomerular menuju kapsul
bowman dengan gradien tekanan tertentu. Cairan yang difiltrasi hartus melewati tiga
lapisan yang membentuk membran glomerulus yaitu dinding kapiler glomerulus, lapisan
gelatinosa aseluler (membran basal), dan lapisan dalam kapsul bowman. Pada dinding
kapiler glomerulus memiliki lubang-lubang dengan banyak pori-pori besar (fenestra) yang
membuatya seratus kali lebih permeabel. Membran basal terdiri dari glikoprotein dan
kolagen. Terselip di antara glomerulus dan kapsul bowman. Glikoprotein ini berfungsi
menghambat filtrasi protein plasma kecil. Dan lapisan terakhir yaitu lapisan dalam kapsul
bowman. Terdiri dari podosit (sel mirip gurita yang mengelilingi berkas glomerulus. Setiap
podosit memiliki tonjolan memanjang yang saling menjalin dengan tonjolan podosit di
dekatnya. Celah sempit diantara tonjolan yang berdekatan dikenal sebagai celah filtrasi,
membentuk jalan bagi cairan untuk keluar dari kepiler glomerulus dan masuk ke lumen
kapsul bowman. Faktor yang membantu filtrasi ini karena membran kapiler glomerular
lebih permeabel dibanding kapiler lain dalam tubuh, tekanan darah dalam kapiler
glomerular lebih tinggi dikarenakan diameter arteriol eferen lebih kecil dibanding diameter
arteriol aferen.
Filtrasi glomerulus disebabkan oleh adanya gaya-gaya fisik pasif yang serupa dengan gaya-
gaya yang terdapat di kapiler tubuh lainnya. Terdapat tiga gaya fisik yang terlibat dalam
40
filtrasi yaitu tekanan darah kapiler glomerulus, tekanan osmotik koloid plasma, dan tekanan
hidrostatik kapsul bowman. Tekanan darah kapiler glomerulus adalah tekanan cairan yang
ditimbulkan oleh darah. Bergantung pada jontraksi jantung dan resistensi arteriol aferen dan
eferen terhadap aliran darah. Tekanan osmotik koloid plasma yang ditimbulkan oleh
distribusi protein plasma yang tidak seimbang dan tekanan hidrostatik kapsul bowman yang
cenderung mendorong cairan keluar dari kapsul bowman ini melawan filtrasi. Tekanan
osmotik yang melawan filtrasi rata-rata besarnya 30 mmHg. Tekanan hidrostatik kapsul
bowman diperkirakan besarnya sekitar 15 mmHg. Gaya total yang mendorong filtrasi
sebesar 55 mmHg, sedangkan jumlah kedua gaya yang melawan arus filtrasi sebesar 45
mmHg. Perbedaan netto yang mendorong filtrasi sebesar 10 mmHg disebut sebagai tekanan
filtrasi netto.
Dan pada setiap harinya, terbentuk rata-rata 180 liter (sekitar 47,5 galon) filtrat glomerulus.
Komposisi filtrat dalam kapsul bowman identik dengan filtrat plasma yang berupa air dan
zat terlarut dengan berat molekul rendah seperti, glukosa,natrium, klorida, kalium, urea,
fosfat, asam urat, dan kreatinin. Sejumlah kecil albumin plasma dapat terfiltrasi namun
sebagian besar diabsorpsi lagi. Sedangkan sel darah merah dan protein tidak difiltrasi.
B. Reabsorpsi Tubulus
Bahan-bahan esensial yang difiltrasi perlu dikembalikan ke darah melalui proses reabsorpsi
tubulus. Reabsorpsi tubulus merupakan suatu proses yang sangat selektif. Hanya sebagian
kecil, itupun kalau ada, dari filtrat yang masih bermanfaat bagi tubuh ditemukan dalam
urin. Hali ini karena sebagian besar telah diabsorpsi dan dikembalikan ke darah melalui
difusi pasif gradien kimia, transpor aktif, atau difusi terfasilitasi. Sekitar 85% filtrat
diabsorpsi dalam tubulus kontortus proksimal, walaupun reabsorpsi berlangsung pada
semua bagian nefron. Beberapa zat yang terabsorpsi yaitu:
- Ion natrium
Ditranspor pasif melalui difusi terfasilitasi dan ditranspor aktif dengan pompa
natrium kalium.
- Ion klor dan ion negatif lain
Ditasnpor pasif dengan difusi.
- Glukosa, froktosa, dan asam amino
41
Melalui kotranspor. Maksimum transporuntuk glukosa adalah jumlah maksimum
yang dapat ditranspor per menit, yaitu sekitar 200 mg glukosa/100 ml plasma. Jika
melebihi, maka glukosa muncul di urin.
- Air
- Urea
50% urea diabsorpsi secara pasif dan 50% diekskresi dalam urin.
- Ion organik lain
Berupa kalium, kalsium, fosfat, sulfat, dan sejumlah ion lain ditranspor aktif.
C. Sekresi Tubular
Adalah proses aktif yang memindahkan zat keluar dari darah dalam kapiler peritubular
melewati sel-sel tubular menuju cairan tubular untuk kemudian keluar bersama urin.
Beberapa zat yang disekresikan berupa:
- Ion hidrogen, kalium, amonium kreatinin, asam hipurat, serta obat-obatan tertentu
aktif disekresi ke tubulus.
- Ion hidrogen dan amonium diganti debgan ion natrium dalam tubulus kantortus distal
dan tubulus pengumpul.
Volume urin yang dihasilkan tiap harinya bervariasi antara 600ml-2.500ml lebih. Jika volume
urin tinggi, maka zat diekskresikan dalam larutan yang encer (hipotonik/ hipoosmotik terhadap
42
plasma. Namun jika tubuh perlu untuk menahan air, maka urin yang dihasilkan kental dan dalam
volume yang sedikit (hipertonik/ hiperosmotik terhadap plasma. Hal ini disebabkan dan diatur
oleh mekanisme hormonal dan mekanisme pengkonsentrasian urine ginjal. Mekanisme hormonal
dipengaruhi oleh hormon ADH (anti diuretic hormone) yang meningkatkan permeabilitas tubulus
kontortus distal dan tubulus pengumpul dan hormon aldosteron. Hormon aldosteron adalah
hormon steroid yang disekresi oleh sel-sel korteks, bekerja ada tubulus distal dan duktus
pengumpul untuk meningkatkan absorpsi ion natrium dan sekresi aktif ion kalium sehingga
meningkatkan retensi air dan garam. Sedangkan mekanisme pengkonsentrasian urine dengan
sistem arus bolak-balik dalam ansa henle dan vase rekta. Memungkinkan terjadinya reabsorpsi
osmotik air sehingga memungkinkan tubuh untuk menahan air sehingga urine yang
diekskresikan lebih kental.
Sedangkan karakteristik urine dapat dirinci dari berbagai segi. Pertama, komposisi urine terdiri
dari 95% air dan mengandung zat terlarut barupa nitrogen, asam hipurat, badan keton, elektrolit,
hormon, berbagai toksin; pigmen; vitamin; atau enzim, konstituen abnormal. Kedua, dari segi
fisik. Warna urine encer berwarna kuning pucat dan kuning pekat jika kental. Bau dari urine
khas dan cenderung berbau amonia. PH urine antara 4,8-7,5 dan berat jenis urine berkisar antara
1, 001-1, 035.
Refleksi
- Pada proses filtrasi, normalnya albumin tidak terfiltrasi. Namun, pada kenyataannya,
ada beberapa kasus yang di dalam urine seseorang terdapat albumin berlebihan
(abuminuria). Hal ini disebabkan oleh gangguan muatan negatif di dalam membran
glomerulus yang menyebabkan membran lebih permeabel terhadap albumin
walaupun ukuran pori-pori tidak berubah.
- Urine diekskresikan untuk membawa zat-zat sisa metabolisme tubuh.
Warna urine akan berwarna pekat jika urine kental. Urine akan kental jika volume
urine sedikit atau zat terlarut lebih banyak. Ini sangat terlihat saat kita sedang sakit
dan meminum obat. Warna urine akan berbeda dengan biasanya ketika tidak
meminum obat.
Infeksi Saluran Kemih
43
Definisi
Pielonefritis akut non komplikata adalah peradangan parenkim dan pelvis ginjal. Definisi
lain adalah sindrom klinis berupa demam, menggigil dan nyeri pinggang yang
berhubungan bakteriuri dan piuri serta tidak memiliki faktor resiko seperti kelainan
struktural dan fungsional saluran kemih atau penyakit yang mendasari yang meningkatkan
resiko infeksi atau kegagalan terapi.1,2
Gejala dan Tanda
Gejala klasik : Demam dan menggigil yang terjadi tiba-tiba, nyeri pinggang unilateral atau
bilateral. Sering disertai gejala sistitis berupa frekuensi, nokturia, disuri, dan urgensi.
Kadang-kadang menyerupai gejala gastrointestinal berupa nausea, muntah, diare atau nyeri
perut. Sebanyak 75% penderita pernah mengalami riwayat ISK bagian bawah.
Secara klinis didapatkan demam (38,5-40OC), takikardi, nyeri ketok pada sudut
kostovertebra. Ginjal seringkali tidak dapat dipalpasi karena nyeri tekan dan spasme otot.
Dapat terjadi distensi abdomen dan ileus paralitik.3
Diagnosis
Urinalisis dilakukan untuk mencari piuria dan hematuria. IDSA melaporkan sebanyak 80
% pyelonefritis akut ditegakkan dengan bakteriuri bermakna > 105 koloni/ml, sedangkan
10-15 % lagi didapatkan dengan bakteriuri bermakna antara 104 - 105 koloni /ml. Oleh
karena itu direkomendasikan bakteriuri bermakna untuk pielonefitis akut adalah > 104
koloni /ml.1,2
Pemeriksaan radiologis
Evaluasi saluran kemih bagian atas dengan USG dan kemungkinan foto BNO untuk
menyingkirkan obstruksi atau batu saluran kemih.
Pemeriksaan tambahan, seperti IVP, CT-scan, seharusnya dipertimbangkan bila pasien
masih tetap demam setelah 72 jam untuk menyingkirkan faktor komplikasi yang lebih jauh
seperti abses renal.
IVP rutin pada pielonefritis akut non komplikata kurang memberikan nila tambah karena
75% menunjukkan saluran kemih normal.1
44
Penatalaksanaan
Antibiotika diberikan selama 7 – 14 hari. Antibiotika yang diberikan sesuai kondisi pasien.
Terapi parenteral dan perawatan diberikan bila kondisi pasien lemah atau sulit untuk
minum. Obat oral dapat diberikan setelah pengobatan hari ke 4.3,4,5
Apabila respons klinik buruk setelah 48-72 jam terapi, dilakukan re-evaluasi bagi adanya
faktor pencetus komplikasi dan efektivitas obat, dipertimbangkan perubahan cara
pemberiannya.3
Follow up
Urinalisis (termasuk dengan dipstik) rutin dilakukan pasca pengobatan. Pada penderita
asimtomatis, kultur rutin pasca pengobatan tidak diindikasikan. Kultur urin ulang
dilakukan 5-7 hari setelah terapi inisial dan 4-6 minggu setelah dihentikan terapi untuk
memastikan bebas infeksi.
Proteus mirabilis
1. Morfologi
Setelah tumbuh selama 24-48 jam pada media
padat, kebanyakan sel seperti tongkat, panjang 1-
3 mm dan lebar 0,4-0,6 mm, walaupun pendek
dan gemuk bentuknya kokus biasa. Dalam kultur
muda yang mengerumun di media padat,
kebanyakan sel panjang, bengkok, dan seperti
filamen, mencapai 10, 20, bahkan sampai
panjang 80 mm. dalam kultur dewasa, organisme
ini tidak memiliki pengaturan karakteristik :
mereka mungkin terdistribusi tunggal,
berpasangan atau rantai pendek. Akan tetapi,
dalam kultur muda yang mengerumun, sel-sel
filamen membentang dan diatur konsentris
seperti isobar dalam diagram angin puyuh.
Kecuali untuk varian tidak berflagella dan flagella yang melumpuhkan, semua jenis
dalam kultur muda aktif bergerak dengan flagella peritrik. Flagella tersebut terdapat
45
dalam bnayak bentuk dibanding kebanyakan enterobakter lain, normal dan bentuk
bergelombang kadang-kadang ditemukan bersama dalam organisme sama dan bahkan
dalam flagellum yang sama. Bentuk flagellum juga dipengaruhi pH media.
2. Klasifikasi
Kingdom : Bacteria
Phylum : Proteobacteria
Class : Gamma Proteobacteria
Order : Enterobacteriales
Family : Enterobacteriaceae
Genus : Proteus
Species : Proteus mirabilis
3. Siklus hidup
Sebenarnya Proteus mirabilis merupakan flora
normal dari saluran cerna manusia. Bakteri ini dapat juga
ditemukan bebas di air atau tanah. Jika bakteri ini
memasuki saluran kencing, luka terbuka, atau paru-paru akan
menjadi bersifat patogen. Perempuan muda lebih beresiko
terkena daripada laki-laki muda, akan tetapi pria dewasa lebih
beresiko terkena daripada wanita dewasa karena
berhubungan pula dengan penyakit prostat. Proteus sering juga
terdapat dalam daging busuk dan sampah serta feses
manusia dan hewan. Juga bisa ditemukan di tanah kebun atau
pada tanaman.
46
Penyakit yang ditimbulkan
Bakteri ini mampu memproduksi enzim urease dalam jumlah besar. Enzim
urease yang menghidrolisis urea menjadi ammonia (NH3) menyebabkan urin bertambah
basa. Jika tidak ditanggulangi, pertambahan kebasaan dapat memicu pembentukan kristal
sitruvit (magnesium amonium fosfat), kalsium karbonat, dan atau apatit. Bakteri ini dapat
ditemukan pada batu/kristal tersebut, bersembunyi dalam kristal dan dapat kembali
menginfeksi setelah pengobatan dengan antibiotik. Semakin banyak batu/kristal
terbentuk, pertumbuhan makin cepat dan dapat menyebabkan gagal ginjal. Proteus
mirabilis memproduksi endotoksin yang memudahkan induksi ke sistem respon inflamasi
dan membentuk hemolisin. Bakteri ini dapat pula menyebabkan pneumonia dan juga
prostatitis pada pria.
1. Gejala
Gejala uretritis tidak terlalu nampak, termasuk frekuensi kencing dan
adanya sel darah putih pada urin. Sistitis (infeksi berat) dapat dengan mudah
diketahui dan termasuk sakit punggung, nampak terkonsentrasi, urgensi, hematuria
(adanya darah merah pada urin), sakit akibat pembengkakan bagian paha atas.
Pneumonia akibat infeksi bakteri ini memiliki gejala demam, sakit pada dada, flu,
sesak napas. Prostatitis dapat diakibatkan oleh infeksi bakteri ini, gejalanya demam,
pembengkakan prostat.
2. Penularan
Infeksi saluran kencing yang disebabkan oleh P. mirabilis juga seringkali
terjadi pada pria dan wanita yang melakukan hubungan seksual tanpa pengaman.
3. Penyebaran
Kebanyakan kasus infeksi Proteus mirabilis terjadi pada pasien di rumah
sakit. Infeksi ini biasanya terjadi karena peralatan media yang tidak steril, seperti
catheters, nebulizers (untuk inhalasi), dan sarung tangan untuk pemeriksaan luka.
Obat yang digunakan
47
Infeksi Proteus mirabilis dapat diobati dengan sebagian besar jenis penisilin
atau sefalosporin kecuali untuk kasus tertentu. Tidak cocok bila digunakan nitrofurantoin
atau tetrasiklin karena dapat meningkatkan resistensi terhadap ampisilin, trimetoprim,
dan siprofloksin. Jika terbentuk batu/kristal, dokter bedah harus menghilangkan blokade
ini dahulu.
DAFTAR PUSTAKA
Hellerstein S. Urinary tract infections. Old and new concepts. Pediatr Clin North Am. Dec 1995;42(6):1433-57. [Medline].
Downs SM. Technical report: urinary tract infections in febrile infants and young children. The Urinary Tract Subcommittee of the American Academy of Pediatrics Committee on Quality Improvement. Pediatrics. Apr 1999;103(4):e54.
Lu KC, Chen PY, Huang FL, et al. Is combination antimicrobial therapy required for urinary tract infection in children?. J Microbiol Immunol Infect. Mar 2003;36(1):56-60. [Medline].
Marild S, Jodal U. Incidence rate of first-time symptomatic urinary tract infection in children under 6 years of age. Acta Paediatr. May 1998;87(5):549-52. [Medline].
Michael M, Hodson EM, Craig JC, et al. Short versus standard duration oral antibiotic therapy for acute urinary tract infection in children. Cochrane Database Syst Rev. 2003;(1):CD003966. [Medline].
Moorthy I, Easty M, McHugh K, et al. The presence of vesicoureteric reflux does not identify a population at risk for renal scarring following a first urinary tract infection. Arch Dis Child. 2005;90:733-6. [Medline]..
Shaw KN, Gorelick M, McGowan KL, et al. Prevalence of urinary tract infection in febrile young children in the emergency department. Pediatrics. Aug 1998;102(2):e16.
48