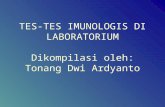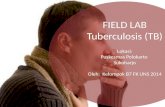Skenario 2 Blok Pediatri 2012 FK UNS
-
Upload
beatadindaseruni -
Category
Documents
-
view
96 -
download
78
description
Transcript of Skenario 2 Blok Pediatri 2012 FK UNS
-
LAPORAN TUTORIAL
BLOK PEDIATRI SKENARIO 2
KELOMPOK 17
TUTOR: Widana P., dr.
Adhe Marlin Sanyoto G0012002
Michael Asby Wijaya G0012132
Wiriyana, I Gst Ngr. Agung G0012132
Helmi Fakhruddin G0012090
Canda Arditya G0012046
Silvia Khasnah G0012212
Ni Nyoman Widyastuti G0012148
Ellena Rachma Kusuma G0012066
Agustin Febriana G0012008
Elvia Rahmi Marga Putri G0012068
Anggraini Lalang Buana G0012016
Azalia Virsalina G0012038
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
TAHUN 2015
-
BAB I
PENDAHULUAN
1. Skenario Anakku batuk dan sulit bernafas
Kasus I
Anto berumur 2,5 tahun. Ibunya membawa berobat ke Puskesmas karena batuk pilek
selama 4 hari. Setelah memeriksa, petugas kesehatan menemukan nadi: 110x/menit,
pernafasan: 32x/menit, suhu: 38,50C. Dokter kemudian memberikan obat.
Kasus II
Seorang anak perempuan berusia 3 tahun dibawa oleh ibunya ke puskesmas karena batuk
sejak 2 hari yang lalu, berdahak putih. Keluhan disertai demam (+). Demam naik turun.
Pada pemeriksaan fisik, nadi: 120x/menit, pernafasan: 52x/menit, suhu: 380C. Saat ini
anak tampak sulit bernafas dan lemah. Terdapat retraksi dinding dada.
Dokter kemudian melakukan tindakan dan merujuk pasien ke rumah sakit untuk
mendapat penanganan dari dokter spesialis anak.
2. Tujuan Pembelajaran a. Membedakan kasus kegawatdaruratan sistem pernafasan pada anak-anak
b. Menjelaskan mekanisme patofisiologis dari sistem pernafasan pada anak-anak
c. Mengetahui diagnosis banding pada kasus batuk, pilek, dan sesak nafas pada anak-
anak
d. Mengetahui tatalaksana pada kasus batuk, pilek, dan sesak nafas pada anak
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
-
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
1. Imunitas Anak Sistem imun merupakan sistem koordinasi respons biologik yang bertujuan
melindungi integritas dan identitas individu serta mencegah invasi organisme dan zat
yang berbahaya dilingkungan yang dapat merusak dirinya. Pada anak dengan usia di
diantara dua bulan sampai dengan tiga tahun, terdapat peningkatan risiko terkena penyakit
serius akibat kurangnya IgG yang merupakan bahan bagi tubuh untuk membentuk sistem
komplemen yang berfungsi mengatasi infeksi. Pada anak dibawah usia tiga tahun pada
umumnya terkena infeksi virus yang berakhir sendiri tetapi bisa juga terjadi bakteremia
yang tersembunyi (bakteremia tanpa tanda fokus). Demam yang terjadi pada anak
dibawah tiga tahun pada umumnya merupakan demam yang disebabkan oleh infeksi
seperti influenza, otitis media, pneumonia, dan infeksi saluran kemih. Bakteremia yang
tersembunyi biasanya bersifat sementara dan dapat sembuh sendiri akan tetapi juga dapat
menjadi pneumonia, meningitis, arthritis, dan pericarditis (Jenson dan Baltimore, 2006).
2. Common Cold a. Definisi dan Epidemiologi
Common cold atau salesma, pada anak-anak sering diidentifikasi sebagai batuk
pilek. Rata-rata anak-anak akan mengalami common cold 6-8 kali per tahun. Seiring
pertambahan usia, frekuensi seorang anak mengalami ini akan semakin menurun,
terutama diatas 6 tahun. Hal ini disebabkan karena perkembangan sistem imun yang
terjadi ditandai dengan peningkatan presentasi sel T memory CD4+ dan CD8+ yang
disensitasi oleh lingkungan.
b. Etiologi dan Patogenesis Common cold ini disebabkan oleh virus, yang paling sering adalah rhinovirus.
Setelah virus tersebut masuk ke dalam tubuh, tubuh akan memunculkan reaksi
terhadap benda asing tersebut yang menyebabkan manifestasi klinis seperti
peningkatan produksi mukus di rongga hidung yang menyebabkan hidung berair,
pembengkakan konka nasalis yang membuat anak susah bernafas, bersin, dan batuk
karena ada peningkatan produksi mukus di tenggorokan.
c. Diagnosis dan Diagnosis Banding Common cold berbeda dengan influenza, perbedaan di antara kedua penyakit ini
sebagai berikut:
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
-
Cold symptoms Flu symptoms
Demam ringan/tidak demam Demam tinggi
Kadang disertai sakit kepala Umumnya ada sakit kepala
Hidung tersumbat Kadang hidung tersumbat
Bersin Kadang bersin
Batuk ringan Batuk tingkat lanjut
Sedikit sakit nyeri Sakit dan nyeri parah
Kelelahan ringan Kelelahan nyata
Radang tenggorokkan Kadang disertai radang tenggorokkan
Tingkat energi normal Kelelahan
d. Penatalaksanaan Untuk mencegah terjadinya batuk pilek pada anak, ada beberapa usaha yang dapat
dilakukan, antara lain menjauhkan anak dari orang-orang disekitarnya yang sedang
menderita cold atau flu, mendidik anak untuk cuci tangan, memastikan mainan anak-
anak bersih terutama yang digunakan anak-anak bermain bersama. Jika sudah terjadi
common cold pada anak, sebaiknya tidak perlu segera diterapi antibiotik, karena
kemungkinan penyebabnya adalah virus. Namun apabila cold ini tidak mendapat
penanganan dan pemantauan yang tepat, ada komplikasi yang mungkin terjadi seperti
infeksi telinga, infeksi tenggorokan, pneumonia, dan infeksi sinus.
3. Pneumonia a. Definisi
Pneumonia adalah suatu radang paru yang disebabkan oleh bermacam-macam etiologi
seperti bakteri, virus, jamur, dan benda asing.Terjadinya pneumonia pada anak sering kali
bersamaan dengan terjadinya proses infeksi akut pada bronkhus yang disebut
bronkopneumonia.
b. Etiologi Menurut publikasi WHO, penelitian di berbagai negara menunjukan bahwa di
negara berkembang Streptokokus pneumonia dan Hemofilus influenza merupakan
bakteri yang selalu ditemukan pada dua pertiga dari hasil isolasi, yaitu 73,9 % aspirat
paru dan 69,1% hasil isolasi dari spesimen darah. Sedangkan di negara maju,
pneumonia pada anak umumnya disebabkan oleh virus.
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
-
Etiologi pneumonia antara lain:
1) Bakteri Diplococcus pneumonia, Pneumococcus, Streptococcus hemolyticus,
Streptococcus aureus, Hemophilus influenza, Bacillus Friedlander.
2) Virus Respiratory syncytial virus, virus influenza, adenovirus, cytomegalovirus.
3) Jamur Mycoplasma pneumoces dermatitides, Coccidioides immitis, Aspergillus, Candida
albicans.
4) Aspirasi Makanan, kerosene (bensin, minyak tanah), cairan amnion, benda asing.
c. Klasifikasi Pembagian pneumonia tidak ada yang memuaskan. Berdasarkan anatomis,
pneumonia dibagi atas:
1) Pneumonia lobaris
2) Pneumonia lobularis (bronkopneumonia)
3) Pneumonia interstitialis (bronkiolitis)
d. Patogenesis Dalam keadaan sehat, pada paru tidak akan terjadi pertumbuhan mikroorganisme.
Keadaan ini disebabkan adanya mekanisme pertahanan paru. Terdapatnya bakteri di
dalam paru menunjukkan adanya gangguan daya tahan tubuh, sehingga
mikroorganisme dapat berkembang biak dan mengakibatkan timbulnya infeksi
penyakit. Masuknya mikroorganisme ke dalam saluran nafas dan paru dapat melalui
berbagai cara, antara lain inhalasi langsung dari udara, aspirasi dari bahan-bahan yang
ada di nasofaring dan orofaring serta perluasan langsung dari tempat-tempat lain,
penyebaran secara hematogen.
1) Stadium (412 jam pertama/ kongesti)
Disebut hiperemia, mengacu pada respon peradangan permulaan yang
berlangsung pada daerah baru yang terinfeksi. Hal ini ditandai dengan
peningkatan aliran darah dan permeabilitas kapiler di tempat infeksi. Hiperemia
ini terjadi akibat pelepasan mediator-mediator peradangan dari sel-sel mast setelah
pengaktifan sel imun dan cedera jaringan. Mediator-mediator tersebut mencakup
histamin dan prostaglandin. Komplemen bekerja sama dengan histamin dan
prostaglandin untuk melemaskan otot polos vaskuler paru dan peningkatan
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
-
permeabilitas kapiler paru. Hal ini mengakibatkan perpindahan eksudat plasma ke
dalam ruang interstisium sehingga terjadi pembengkakan dan edema antar kapiler
dan alveolus. Penimbunan cairan di antara kapiler dan alveolus meningkatkan
jarak yang harus ditempuh oleh oksigen dan karbondioksida, sehingga
mempengaruhi perpindahan gas dalam darah dan sering mengakibatkan
penurunan saturasi oksigen hemoglobin.
2) Stadium II (48 jam berikutnya)
Disebut hepatisasi merah, terjadi sewaktu alveolus terisi oleh sel darah merah,
eksudat dan fibrin yang dihasilkan oleh penjamu ( host ) sebagai bagian dari
reaksi peradangan. Lobus yang terkena menjadi padat oleh karena adanya
penumpukan leukosit, eritrosit dan cairan, sehingga warna paru menjadi merah
dan pada perabaan seperti hepar, pada stadium ini udara alveoli tidak ada atau
sangat minimal sehingga anak akan bertambah sesak, stadium ini berlangsung
sangat singkat, yaitu selama 48 jam.
3) Stadium III (38hari)
Disebut hepatisasi kelabu yang terjadi sewaktu sel-sel darah putih
mengkolonisasi daerah paru yang terinfeksi. Pada saat ini endapan fibrin
terakumulasi di seluruh daerah yang cedera dan terjadi fagositosis sisa-sisa sel.
Pada stadium ini eritrosit di alveoli mulai diresorbsi, lobus masih tetap padat
karena berisi fibrin dan leukosit, warna merah menjadi pucat kelabu dan kapiler
darah tidak lagi mengalami kongesti.
4) Stadium IV (711hari)
Disebut juga stadium resolusi yang terjadi sewaktu respon imun dan
peradangan mereda, sisa-sisa sel fibrin dan eksudat lisis dan diabsorsi oleh
makrofag sehingga jaringan kembali ke strukturnya semula.
e. DIAGNOSIS 1) Anamnesis
Pasien biasanya mengalami demam tinggi, batuk, gelisah, rewel dan sesak
nafas. Pada bayi, gejalanya tidak khas, sering kali tanpa demam dan batuk. Anak
besar biasanya mengeluh nyeri kepala dan muntah.
2) Pemeriksaan Fisik
Manifestasi klinis yang terjadi berbeda-beda sesuai kelompok umur tertentu.
Pada neonates sering terjadi takipneu, retraksi dinding dada, grunting dan sianosis.
Pada bayi yang lebih tua jarang ditemukan grunting. Gejala yang sering terlihat
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
-
adalah takipneu, retraksi, sianosis, batuk, panas, dan iritabel. Pada anak pra
sekolah, gejala yang sering terjadi adalah demam, batuk (non produktif/produktif),
takipneu, dan dispneu yang ditandai dengan retraksi dinding dada. Pada kelompok
anak sekolah dan remaja, dapat dijumpai panas, batuk (non produktif/produktif),
nyeri dada, nyeri kepala, dehidrasi dan letargi. Pada semua kelompok umur, akan
dijumpai pernafasan cupping hidung. Pada auskultasi, dapat terdengar suara
pernafasan menurun. Fine crackles (ronki basah halus) yang khas pada anak besar
bisa saj tidak ditemukan pada anak bayi. Gejala lain pada anak besar adalah dull
(redup) pada perkusi, fremitus menurun, dan terdengar Fine crackles di daerah
yang terkena. Iritasi pleura akan menyebabkan nyeri dada. Bila berat, gerakan
dada menurun saaat inspirasi, anak berbaring ke arah yang sakit dengan kaki
fleksi. Rasa nyeri dapat menjalar ke leher, bahu, dan perut.
f. Pemeriksaan Penunjang 1) Ro torak PA merupakan dasar diagnosis utama pneumonia
2) Leukosit>15.000/ul, dengan didominasi sel neutrofil
3) Trombositopenia bisa didapatkan pada pneumonia dengan empiema
4) Pemeriksaan sputum kurang berguna
5) Biakan darah jarang positif (3 11%) kecuali untuk Pneumokokus dan
H.Influenzae (25 95%)
6) Rapid test untuk deteksi antigen bakteri mempunyai sensitifitas dan spesifisitas
rendah.
7) Pemeriksaan serologis kurang bermanfaat
g. Diagnosis Banding 1) Bronkiolitis
Bronkiolitis adalah infeksi virus akut saluran pernapasan bawah yang
menyebabkan obstruksi inflamasi bronkiolus, terjadi terutama pada anak-anak
dibawah umur 2 tahun, dengan insidensi tertinggi pada bayi berusia 6 bulan.
Penyebab yang paling banyak adalah Respiratory Sensitial Virus (RSV), kira-kira
45-80 % dari total kasus bronkiolitis akut.
Bayi dengan bronkiolitis akut mula-mula menderita gejala infeksi saluran
napas atas yang ringan berupa pilek yang encer, batuk, dan bersin, kadang-kadang
disertai demam yang tidak terlalu tinggi (subfebrile) dan nafsu makan berkurang.
Gejala ini berlangsung beberapa hari. Kemudian timbul distres respirasi yang
ditandai oleh batuk paroksismal, wheezing, sesak napas. Bayi-bayi akan menjadi
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
-
rewel, muntah serta sulit makan dan minum. Timbulnya kesulitan minum terjadi
karena napas cepat sehingga menghalangi proses menelan dan menghisap. Pada
kasus ringan, gejala menghilang 13 hari. Pada kasus berat, gejalanya dapat
timbul beberapa hari dan perjalanannya sangat cepat.
Kadang-kadang, bayi mengalami demam ringan atau tidak demam sama
sekali, bahkan ada yang mengalami hipotermi. Terjadi distres pernapasan dengan
frekuensi napas >60 x/menit, terdapat napas cuping hidung, penggunaan otot
pernapasan tambahan, retraksi, dan kadang-kadang disertai sianosis. Karena bayi
mempunyai dinding dada yang lentur, retraksi suprasternal dan kosta tampak jelas
dan tepi kosta terlihat melebar pada setiap pernafasan untuk menambah volume
tidalnya. Retraksi biasanya tidak dalam karena adanya hiperinflasi paru
(terperangkapnya udara dalam paru). Hepar dan lien bisa teraba karena terdorong
diafragma akibat hiperinflasi paru. Mungkin terdengar ronki pada akhir inspirasi
dan awal ekpirasi. Terdapat ekpirasi yang memanjang dan wheezing kadang-
kadang terdengar dengan jelas. Sering terjadi hipoksia dengan saturasi oksigen
-
Bila anak mengalami hipoksia, anak tampak gelisah, tetapi jika hipoksia
bertambah berat anak tampak diam, lemas, kesadaran menurun. Pada kondisi yang
berat dapat menjadi gagal napas. Pada kasus yang berat proses penyembuhan
terjadi setelah 7-14 hari1. Anak akan sering menangis, rewel, dan akan merasa
nyaman jika duduk di tempat tidur atau digendong (Rahajoe et al., 2008).
h. Tatalaksana Diagnosis etiologi pneumonia sangat sulit untuk dilakukan, sehingga pemberian
antibiotik diberikan secara empirik sesuai dengan pola kuman tersering yaitu
Streptococcus pneumonia dan H. influenza. Pemberian antibiotik sesuai kelompok
umur. Untuk umur dibawah 3 bulan diberikan golongan penisilin dan aminoglikosida.
Untuk usia > 3 bulan, pilihan utama adalah ampisilin dipadu dengan kloramfenikol.
Bila keadaan pasien berat atau terdapat empiema, antibiotik adalah golongan
sefalosporin. Antibiotik parenteral diberikan sampai 48-72 jam setelah panas turun,
dilanjutkan dengan pemberian per oral selama 7 10 hari. Bila diduga penyebab
pneumonia adalah S.aureus, kloksasilin dapat segera diberikan. Bila alergi terhadap
penisilin dapat diberikan cefazolin, klindamisin, atau vancomycin. Lama pengobatan
untuk Stafilokokus adalah 3 4 minggu
4. Tanda Vital Pediatri a. Frekuensi Pernapasan (Respiratory Rate)
Adapun kriteria normal frekuensi pernapasan pada neonatus dan anak menurut
usia sebagai berikut (WHO, 2009):
< 1 tahun : 30 40 kali/menit
2 5 tahun : 20 30 kali/menit
5 12 tahun : 15 - 20 kali/menit
> 12 tahun : 12 16 kali/menit
Namun, apabila anak datang dengan frekuensi pernapasan di atas nilai normal
tidak dapat secara langsung didiagnosis takipneu, dimana kriteria nafas cepat
(takipneu) menurut usia sebagai berikut (WHO, 2009):
< 2 bulan : > 60 kali/menit
2 12 bulan : > 50 kali/menit
1 5 tahun : > 40 kali/menit
> 5 tahun : > 30 kali/menit
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
-
b. Denyut Nadi (Heart Rate) Pada bayi dan anak, ada atau tidaknya denyut nadi utama yang kuat sering
merupakan tanda berguna untuk melihat ada tidaknya syok dibandingkan mengukur
tekanan darah. Nilai normal denyut nadi pada anak menurut usia, yaitu:
0 3 bulan : 85 200 kali/menit
3 bulan 2 tahun : 100 190 kali/menit
2 10 tahun : 60 140 kali/menit
Pada anak yang sedang tidur denyut nadi normal 10% lebih lambat (WHO, 2009)
c. Tekanan Darah Tekanan darah normal pada anak menurut usia antara lain (WHO, 2009):
0 1 tahun : > 60 mmHg
1 3 tahun : > 70 mmHg
3 6 tahun : > 75 mmHg
d. Suhu Tubuh Menurut Buku Panduan Manajemen Balita Sakit Terpadu (2008), anak dikatakan
demam jika suhu tubuhnya 37,5oc.
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
ellena
-
BAB III
PEMBAHASAN
Pada kasus I diketahui bahwa denyut nadi dan RR anak termasuk normal, mengalami
demam, serta menderita batuk pilek selama 4 hari. Berdasarkan hasil pemeriksaan
tersebut salah satu diagnosis yang didapatkan adalah common cold. Pada common cold
didapatkan adanya rhinorrhea yang menonjol yang juga disebutkan pada kasus. Gejala
sistemik lain dapat bervariasi; seperti pusing, myalgia, serta mild fever (terkadang dapat
ditemui keadaan tanpa demam) (Kliegmann et al., 2011).
Gejala dari common cold biasanya terjadi 1-3 hari setelah infeksi virus. Pada awalnya
muncul hanya sebagai rasa gatal pada tenggorokan, kemudian muncul rhinorrhea. Batuk
biasanya muncul setelah onset rhinorrhea. Biasanya gejala-gejala tersebut berlangsung
sampai dengan 1 minggu, atau 2 minggu. Pada anak usia tersebut common cold sering
didapati, dikarenakan belum sempurnanya imun anak (Kliegmann et al., 2011).
Pada kasus I kemungkinan diagnosis bandingnya adalah common cold. di sini dokter
dapat memberikan Anti Histamin tipe 1 generasi 1 dengan dengan mengggunakan efeks
sedasinya agar anak tenang dan tidak rewel. Pemeberian antihistamin dan dekongestan
ataupun kombinasi antihistamin-dekongestan tidak direkomendasikan untuk anak kurang
dari 6 tahun karena adanya efek samping obat dan kurangnya manfaat yang diberikan
(Marcdante et al., 2011).
Selain antihistamin tipe 1 generasi 1, dokter dapat memberikan antipiretik untuk
demam lebih dari 38,5oC (ada sumber lain mengatakan 38,3OC) antipiretik yang dapat
diberikan antara lain paracetamol (asetaminofen) atau ibuprofen. Parasetamol diberikan
karena memiliki efek menurunkan panas dan mengurangi rasa sakit.Dosis yang dapat
diberika pada balita usia 3 tahun adalah 10-15 mg/kg berat badan secara peroral setiap 4-6
jam, dengan dosis maksimal 2,6 gram/hari. Pilihan lain yang dapat diberikan adalah
ibuprofen, yang selain memiliki efek antipiretik, ibuprofen memiliki efek antiinflamasi.
Dosis yang dapat diberikan untuk anak usia 3 tahun (6 bulan hingga 12 tahun) 5-10
mg/kg berat badan/dosis peroral dengan pemberian setiap 6-8 jam tidak lebih dari 40
mg/kg berat badan setiap harinya (Windle et al., 2015).
Pada kasus II, disebutkan bahwa pasien adalah anak perempuan berusia 3 tahun
dengan keluhan batuk 2 hari, berdahak putih, dan demam naik turun. Pada pemeriksaan
fisik didapatkan nadi 120 kali/menit, nafas 52 kali/menit, suhu tubuh 38 derajat celcius.
Dalam Panduan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) tahun 2008, disebutkan bahwa
pada anak berusia 2 bulan hingga kurang dari 12 bulan, napas tergolong cepat bila
ellena
ellena
-
frekuensinya 50 kali atau lebih per menit, dan 40 kali atau lebih per menit untuk anak
berusia 12 bulan hingga kurang dari 5 tahun. Anak juga tergolong demam bila didapatkan
laporan dari pengantar saat anamnesis atau anak teraba panas atau suhu 37,5C. Maka
dapat diketahui bahwa pasien mengalami demam dan napas cepat.
Dalam Panduan MTBS juga disebutkan anda bahaya umum pada anak, yaitu anak
tidak mau minum/menyusu, anak selalu memuntahkan makanannya, kejang, dan tampak
letargis. Dalam skenario, disebutkan bahwa anak tampak sulit bernafas dan lemah, serta
terdapat retraksi dinding dada.
Retraksi dinding dada merupakan tanda di mana seseorang mengalami kesulitan untuk
bernapas. Retraksi dinding dada juga dikenal dengan istilah tarikan dinding dada bagian
bawah ke dalam . Kesulitan untuk bernapas pada anak bisa disebabkan oleh tiga causa
yang berbeda, antara lain obstruksi saluran pernapasan atas seperti croup, obstruksi
saluran pernapasn bawah seperti asma dan bronchiolitis, dan penyakit jantung parenkimal
seperti pneumonia, edema pulmonal, serta sindrom distress pernapasan akut. Pada anak
dengan pneumonia terjadi penurunan kemampuan paru untuk berkembang sebagaimana
mestinya. Hal ini membuat tubuh untuk merespon kekurangan oksigen yang ada di paru-
paru untuk bernapas lebih cepat. Akan tetapi dengan kondisi paru-paru yang kaku oleh
fibrin dan disertai dengan konsolidasi alveoli menyebabkan paru akan tetap kesulitan
untuk berkembang. Akibatnya timbul tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam. Anak
dengan kasus pneumonia yang berat biasanya akan mengalami retraksi dinding dada.
Akan tetapi retraksi ini tidak selalu disertai dengan pernapasan cepat dikarenakan anak
sudah kehabisan energi untuk bernapas. Hal ini merupakan tanda bahaya dikarenakan
insidensi kematian yang tinggi. Hal tersebut mengarahkan dugaan menuju pneumonia
berat atau penyakit sangat berat.
Diagnosis banding yang mungkin berdasarkan gejala serta temuan klinis yang
didapatkan dari anak pada kasus II antara lain pneumonia, bronkiolitis, dan croup. Namun
dari ketiga diagnosis banding tersebut, belum dapat ditegakkan diagnosis kerja.
Diperlukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan lab dan radiologi untuk dapat
menegakkan diagnosis.
Pada kasus II, pasien dapat diberikan terapi antibiotik secara empiris dengan pilihan
cotrimoxazole, amoxicillin, atau gentamisin. Cotrimoxazol untuk dosis anak berusia 3
tahun adalah 8 mg TMP/kg berat badan/ hari peroral dibagi untuk setiap 12 jam pada
kasus infeksi ringan. sedangkan untuk infeksi serius dapat diberikan 15-20 mg TMP/kg
ellena
-
berat badan/hari dibagi setiap 6 jam. Cotrimoxazole kontra indikasi untuk bayi berusia
kurang dari 2 bulan (Windle et al, 2015).
Untuk pengobatan usia lebih dari 3 bulan dengan berat badan kurang dari 40 kg,
amoxicillin dapat diberikan secara peroral sebanyak 25 mgkg berat badan/hari dibagi
setiap 12 jam atau 20mg/kg berat badan/ hari dibagi setiap 8 jam untuk infeksi ringan,
sedangkan untuk infeksi berat dapat diberikan obat 45 mg/kg/hari setiap 12 jam atau 40
mg/kg/hari setiap 8 jam. Gentamisin dapat diberikan secara intravena atau intra muskular
sebanyak2,5 mg/mg/dosis setiap 8 jam. Selain antibiotik, pasien dapat diberikan anti
piretik dengan dosis yang sama dengan kasus 1 (karena jangkauan umur masih sama).
(Windle et al, 2015).
-
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan a. Pada kasus I, didapatkan pasien dengan identitas Anto, usia 2,5 tahun, keluhan
batuk pilek sejak 4 hari. Vital Sign didapatkan denyut nadi dan frekuensi
pernafasan dalam batas normal, pasien sedikit demam. Diagnosis banding adalah
commoncold. Tatalaksana yang diberikan berupa pemberian obat antihistamin
generasi I dan antipiretik.
b. Pada kasus II, didapatkan pasien anak perempuan dengan usia 3 tahun, keluhan
batuk dahak putih sejak 2 hari dan disertai naik turun. Vital sign didapatkan
denyut nadi batas normal, takipneu, dan pasien sedikit demam. Pemeriksaan fisik:
lemah; sulit bernapas; etraksi dinding dada. Diagnosis banding adalah pneumonia,
bronkiolitis, dan croup. Tindakan yang dilakukan merujuk pasien ke rumah sakit
(Dokter Spesialis Anak), dimana dapat diberikan antibiotik empiris seperti
kotrimoksazol, dll.
2. Saran Saran yang dapat diberikan adalah mahasiswa diharapkan mencari bahan tutorial
dengan membaca buku-buku kedokteran, jurnal, dsb sebelum tutorial sehingga
tutorial bisa berjalan lebih lancar dan baik.
-
BAB V
DAFTAR PUSTAKA
Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2008). Panduan Manajemen Tatalaksana
Bayi Sakit. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia
http://saripediatri.idai.or.id/pdfile/3-3-6.pdf. Diunduh Maret 2015
http://old.pediatrik.com/pkb/061022023132-f6vo140.pdf. Diunduh Maret 2015
http://www.hopkinsmedicine.org/healthlibrary/conditions/pediatrics/upper_respiratory_in
fection_uri_or_common_cold_90,P02966/. Diunduh Maret 2015
Jenson HB dan Baltimore RS (2006). Pneumonia. Dalam: Kliegman RM, Marcdante KJ,
Jenson HB, Behrman RE. Nelson Essential of Pediatrics 5 Edition. Philadelphia:
Elsevier
Kliegmann RM et al. (2011). Nelson Textbook of Pediatrics Nineteenth Edition.
Philadelphia: Elsevier
Marcdante KJ, Kliegman RM, Jenson HB, Behrman RE (2011). Ilmu Kesehatan Anak
Esensial Nelson Edisi Keenam. Jakarta: Elsevier
Rahajoe NN, Supriyatno B, Setyanto DB (2008). Buku Ajar Respirologi Anak Edisi
Pertama. Jakarta: IDAI, pp: 320-328
Windle et al. (2015). Medscape: Pediatric oral dosing. Emedecine.medscape.com/article.
Diunduh Maret 2015.
World Heatlh Organization (2009). Pelayanan Kesehatan Anak di Rumah Sakit, Pedoman
Bagi Rumah Sakit Rujukan Tingkat Pertama di Kabupaten/Kota. Jakarta: WHO
Indonesia.