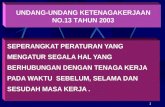demonstrasi yang dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh ...
Serikat pekerja dan organisasi pengusaha di indonesia
-
Upload
tae-kwon-do-um -
Category
Education
-
view
457 -
download
7
Transcript of Serikat pekerja dan organisasi pengusaha di indonesia
1. Serikat Pekerja dan Organisasi Pengusaha di Indonesia SPI pada dasarnya muncul sebagai alat perjuangan kemerdekaan terhadap penjajah Belanda dengan bekerja sama atau mengikatkan diri kepada partai politik. Setelah kemerdekaan, organisasi tersebut tidak menyesuaikan diri menjadi sosial ekonomi melainkan tetap menjadi organisasi sosial ekonomi. Kemudian pada tahun 1961, dalam rangka memupuk kerjasama kaum pekerja, maka dibentuklah Serikat Buruh bernama SOBSI dibawah parati politik induk PKI. Akan tetapi pada tahun 1965 dibubarkan sehubungan dengan gencarnya upaya pemberantasan PKI. Selanjutnya, dibentuk Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI) yang pada ahirnya berubah menjadi Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI) yang beranggotakan Serikat BUruh Vaksentral dan 15 BUruh non-vaksentral. Dalam bentuk kerjasama ini, kebebasan dan kedaulatran masih tetap berada di tangan masing-masing buruh dan pekerja, dan sebagian besar anggota serikat pekerja masih terikat kepada parpol tertentu. Perubahan fundamental pada serikat buruh baru terjadi pada tahun 1973 dengan didirikannya Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). Tujuannya menitikberatkan pada aspek sosial ekonomi pekerja, bukan aspek politik. Serikat pekerja ini disusun berdasarkan lapangan kerja atau profesi seperti Serikat Buruh Pertanian dan Perkebunan (SBPP), Serikat Buruh Rokok dan Tembakau (SBRT), Serikat Buruh Kesehatan (SBK), Perhimpunan Guru Indonesia (PGI), dan lain-lain. Golongan pegawai negeri dan ABRI tidak diperkenankan menjadi pengurus dari FBSI atau suatu SBLP(Serikat BUruh LApangan Pekerjaan). Organisasi pengusaha sendiri di Indonesia teah terbentuk sejak tahun 1952 bernama Industriele Bond yang beranggotakan perusahaan-perusahaan Belanda dan Central Stichtung Werkgevers Overleg (CSWO) yang beranggotakan campuran perusahaan-perusahaan asing Amerika, Inggris, dan Belanda. Kemudian pada tahun 1975 sehubungan dengan aksi pembebasan Irian Barat, pemerintah mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda sehingga organisasi pengusaha ini akhirnya bubar kecuali CSWO yang tetap terus berdiri. CSWO kemudian ikut membubarkan diri pada tahun 1963 dan untuk mengisi kekososngan tersebut maka didirikanlah Yayasan Permusyawaratan Urusan Sosial Pengusaha di Indonesia (PUSPI). 2. Pada Maret 1969 PUSPI berubah bentuk dari yayasan menjadi organisasi dan pada bulan mei merubah namanya menjadi Permusyawaratan Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia. Dalam kongresnya bulan Februari 1985, organisasi ini berubah nama kembali menjadi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Disamping APINDO atau PUSPI, pengusah- pengusaha di Indonesia juga tergabung dalam Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Kadin lebih menitikberatkan aspek ekonomi perusahaan dan PUSPI lebih menitikberatkan aspek kesejahteraan sosial pengusaha. Pengaruh Upah Minimal dalm Pasar Kerja Dalam pembahasan pasar kerja, selalu diasumsikan terdapat keseimbangan antar permintaan dengan penawaran tenaga kerja pada tingkat upah tertentu dengan jumlah tenaga kerja tertentu. Namun pada kenyataannya keseimbangan ini tidak selamanya menunjukkan tingkat upah yang terjadi di pasar kerja, khususnya bila ada campur tangan pemerintah ataupun desakan serikat pekerja untuk menentukan upah minimum. Dalam teori mengenai pasar kerja yang ditandai dengan persaingan, diperkirakan pengenaan upah minimal yang efektif akan mempengaruhoi jumlah tenaga kerja. Upah D S Um a b Ue TKm 3. Jumlah Tenaga Kerja 0 TKe Gambar : Pengaruh upah minimal dalam pasar persaingan sempurna Kurva permintaan tenaga kerja (D) dan kurva penawarannya (S) bertemu dan menunjukkan keseimbangan upah pada Ue dan banykanya tenaga kerja yang dipekerjakan TKe. Apabila ditetapkan upah minimum sebesar Um yang berada diatas upah riil yang terjadi di pasar Ue, maka jumlah tenaga kerja yang dikerjakan akan berkurang dari TK eke titik TKm. Pengurangan pekerja sebesar TKe TKm ini lebih kecil dari kelebihan penawaran tenaga kerja akibat penetapan upah minimum. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya orang yang ingin masuk pasar kerja bila mendengar upah dinaikkan, namun harapan mereka ini tampak sia-sia belaka, karena gambar tersebut menunjukkan bila upah dinaikkan maka pengusaha akan berusaha mengurangi pekerjanya. Sehingga orang-orang yang ingin bekerja dengan tingkat upah yang baru tersebut(Um), tidak dipekerjakan. Keadaan ini menyebabkan sebagian orang kehilangan pekerjaannya. Garis ab, dan yang lain mungkin bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah dari Um, seperti ditunjukkan dengan garis bc. Ukuran dari kedua komponen ini, dan bc sangat tergantung pada kemiringan kurva penawaran dan permintaan tenaga kerja. Analisa semacam ini akan berguna dalam keadaan terdapat informasi yang sempurna baik bagi pengusaha maupun pekerja serta terdapatnya mobilitas yang sempurna pula bagi para pekerja itu sendiri. Selain itu, perlu diperhatikan pula factor-faktor lain diluar upah yang akan mempengaruhi tingkat keseimbangan tersebut. Penetapan upah minimal oleh pemerintah seperti pada kasus tersebut akan sam dampaknya bila serikat pekerja di negara-negara yang menganut system ekonomi liberal berusaha menaikkan tingkat upah. Di negar-negar ini peranan serikat pekerja begitu penting sehingga mempengaruhi alokasi sumberdaya yang ada. Dampak Adanya Serikat Pekerja Pada Alokasi Sumber Daya Dalam upaya serikat pekerja untuk merubah pendapatan pekerja, secara tidak langsung juga mempengaruhi alokasi pekerja dalam berbagai sector ekonomi dan mungkin juga 4. menyebabkan timbul hilangnya kesejahteraan umum (welfare losses) ataupun kerugian dalm total output sebagai akibat kesalahan alokasi pekerja (missallocation of labor). Upah S Ds Dts Dk Us Ue a b Uts d c 5. TK so TK ts1 0 Jumlah TK TK s1 TK tso Gambar : Dampak perbedaan upah akibat adanya Serikat pekerja pada alokasi sumber daya Keterangan pada kurva tersebut diatas menjelaskan, misalkna pad perekonomian terdapat tenaga kerja yang seragam dan tetap pada kurva S1, sehingga tidak terpengaruh oleh tingkat upah. Perekonomian ini terbagi atas sektor S dan TS yang pada awalnya keduanya tidak memilikiserikat pekerja. Permintaan tenaga kerja pada kedua sektor ini diwakili oleh garis-garis parallel Ds dan D ts, yang penjumlahannya secara horizontal adalah Dk yang menunjukkan jumlah keseluruhan permintaan tenaga kerja. Pada mulanya tingkatbupah terjadi secara competitive pada tingkat Ue untuk kedua sektor ini. Jumlah pekerja sebanyak TK so untuk sektor S dan TK tso bagi sektor TS, kemudian S memilki serikat pekerja yang setelah melalui proses tawar-mew=nawar dengan pihak pengusaha berhasil menaikkan upah menjadi ke tingkat Us. Akibatnya jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sektor S berkurang sebesar OTK s1 saja, jika diasumsikan pekerja yang kehilangan pekerjaannya ini berpindah bekerja pada sektor yang tidak memilki serikat pekerja, yaitu sektor T. agar bias tetap menghidupi keluarganya maka jumlah pekerja yang ingin bekerja pada sektor TS meningkat dari semula hanya OTK tso menjadi OTK ts1. Sebagai akibatnya, ceteris paribus, ditingkat upah yang terjadi pada sektor TS ini turun dari titik Ue kea rah titik U ts. Dalam hubungan ini tampak sektor S yang memiliki serikat pekerja menjadi kurang padat karya, sementara sektor TS yang tetap tanpa ada serikat pekerja lebih banyak bias menyerap tenaga kerja. Apabila diperhitungkan bagian bawah masing-masing kurva permintaan pekerja merupakan total product dari sektor yang bersangkutan, denga asumsi kurva permintaan pekerja berdasar pada nilai dari produk marginal, maka bias diperhitungkan kerugian yang diderita perekonomian akibat keadaan di atas. 6. TK so TK ts1 0 Jumlah TK TK s1 TK tso Gambar : Dampak perbedaan upah akibat adanya Serikat pekerja pada alokasi sumber daya Keterangan pada kurva tersebut diatas menjelaskan, misalkna pad perekonomian terdapat tenaga kerja yang seragam dan tetap pada kurva S1, sehingga tidak terpengaruh oleh tingkat upah. Perekonomian ini terbagi atas sektor S dan TS yang pada awalnya keduanya tidak memilikiserikat pekerja. Permintaan tenaga kerja pada kedua sektor ini diwakili oleh garis-garis parallel Ds dan D ts, yang penjumlahannya secara horizontal adalah Dk yang menunjukkan jumlah keseluruhan permintaan tenaga kerja. Pada mulanya tingkatbupah terjadi secara competitive pada tingkat Ue untuk kedua sektor ini. Jumlah pekerja sebanyak TK so untuk sektor S dan TK tso bagi sektor TS, kemudian S memilki serikat pekerja yang setelah melalui proses tawar-mew=nawar dengan pihak pengusaha berhasil menaikkan upah menjadi ke tingkat Us. Akibatnya jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sektor S berkurang sebesar OTK s1 saja, jika diasumsikan pekerja yang kehilangan pekerjaannya ini berpindah bekerja pada sektor yang tidak memilki serikat pekerja, yaitu sektor T. agar bias tetap menghidupi keluarganya maka jumlah pekerja yang ingin bekerja pada sektor TS meningkat dari semula hanya OTK tso menjadi OTK ts1. Sebagai akibatnya, ceteris paribus, ditingkat upah yang terjadi pada sektor TS ini turun dari titik Ue kea rah titik U ts. Dalam hubungan ini tampak sektor S yang memiliki serikat pekerja menjadi kurang padat karya, sementara sektor TS yang tetap tanpa ada serikat pekerja lebih banyak bias menyerap tenaga kerja. Apabila diperhitungkan bagian bawah masing-masing kurva permintaan pekerja merupakan total product dari sektor yang bersangkutan, denga asumsi kurva permintaan pekerja berdasar pada nilai dari produk marginal, maka bias diperhitungkan kerugian yang diderita perekonomian akibat keadaan di atas.