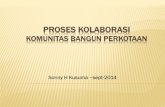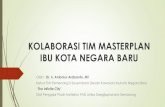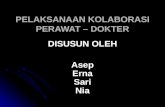QBL 2 kolaborasi
-
Upload
riketriana -
Category
Documents
-
view
9 -
download
1
description
Transcript of QBL 2 kolaborasi

QBL 2 – KOLABORASIOleh Rike Triana, 1406571483
TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT
1. DefinisiKesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang
hidup dan meningkatkan kesehatan melalui pengorganisasian masyarakat untuk perbaikan sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit menular, pendidikan kesehatan dan sebagainya (Winslow, 1920). Inti rumusan batasan kesehatan masyarakat tersebut adalah kesehatan masyarakat mempunyai dua aspek, yakni : keilmuan (science), teori dan seni (art) atau aplikasinya.
Berdasarkan Naskah Akademik Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat, definisi kesmas sebagai ilmu adalah kombinasi dari ilmu pengetahuan, keterampilan, moral dan etika, yang diarahkan pada upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat, memperpanjang hidup melalui tindakan kolektif, atau tindakan social, untuk mencegah penyakit dan memenuhi kebutuhan menyeluruh dalam kesehatan, dengan menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri.
Rancangan karakter tenaga kesehatan masyarakat profesional diantaranya MIRACLE (Manager, Innovator, Researcher, Aprenticer, Communitarian, Leader, Educator).
2. Sejarah PerkembanganPerkembangan ilmu kesehatan masyarakat saat ini terbukti tetap mempertahankan
rumpun ilmu, sebagaimana perkembangan kesmas di Indonesia dengan kecirian rumpun ilmu yang disebut peminatan. Sejarah ini harus terus berkembang dan tidak harus didegradasi karena alasan-alasan administratif dan birokrasi pendidikan. Karena itu, kecirian rumpun ilmu harus dipertahankan karena kelompok keilmuanlah yang paling tahu dan memahami perkembangan ilmunya.
Perkembangan Kesehatan Masyarakat di IndonesiaAbad Ke-16 – Pemerintahan Belanda mengadakan upaya pemberantasan cacar dan
kolera yang sangat ditakuti masyarakat pada waktu itu. Sehingga berawal dari wabah kolera tersebut maka pemerintah Belanda pada waktu itu melakukan upaya-upaya kesehatan masyarakat.
Tahun 1807 – Pemerintahan Jendral Daendels, telah dilakukan pelatihan dukun bayi dalam praktek persalinan. Upaya ini dilakukan dalam rangka upaya penurunan angka kematian bayi pada waktu itu, tetapi tidak berlangsung lama, karena langkanya tenaga pelatih.
Tahun 1888 – Berdiri pusat laboratorium kedokteran di Bandung, yang kemudian berkembang pada tahun-tahun berikutnya di Medan, Semarang, surabaya, dan

Yogyakarta. Laboratorium ini menunjang pemberantasan penyakit seperti malaria, lepra, cacar, gizi dan sanitasi.
Tahun 1925 – Hydrich, seorang petugas kesehatan pemerintah Belanda mengembangkan daerah percontohan dengan melakukan propaganda (pendidikan) penyuluhan kesehatan di Purwokerto, Banyumas, karena tingginya angka kematian dan kesakitan.
Tahun 1927 – STOVIA (sekolah untuk pendidikan dokter pribumi) berubah menjadi sekolah kedokteran dan akhirnya sejak berdirinya UI tahun 1947 berubah menjadi FKUI. Sekolah dokter tersebut punya andil besar dalam menghasilkan tenaga-tenaga (dokter-dokter) yang mengembangkan kesehatan masyarakat Indonesia.
Tahun 1930 – Pendaftaran dukun bayi sebagai penolong dan perawatan persalinan.Tahun 1935 – Dilakukan program pemberantasan pes, karena terjadi epidemi,
dengan penyemprotan DDT dan vaksinasi massal.Tahun 1951 -Diperkenalkannya konsep Bandung (Bandung Plan) oleh Dr.Y.
Leimena dan dr Patah (yang kemudian dikenal dengan Patah-Leimena), yang intinya bahwa dalam pelayanan kesehatan masyarakat, aspek kuratif dan preventif tidak dapat dipisahkan. konsep ini kemudian diadopsi oleh WHO. Diyakini bahwa gagasan inilah yang kemudian dirumuskan sebagai konsep pengembangan sistem pelayanan kesehatan tingkat primer dengan membentuk unit-unit organisasifungsional dari Dinas Kesehatan Kabupaten di tiap kecamatan yang mulai dikembangkan sejak tahun 1969/1970 dan kemudian disebut Puskesmas.
Tahun 1952 – Pelatihan intensif dukun bayi dilaksanakanTahun 1956 – Dr.Y.Sulianti mendirikan “Proyek Bekasi” sebagai proyek
percontohan/model pelayanan bagi pengembangan kesehatan masyarakat dan pusat pelatihan, sebuah model keterpaduan antara pelayanan kesehatan pedesaan dan pelayanan medis.
Tahun 1967 – Seminar membahas dan merumuskan program kesehatan masyarakat terpadu sesuai dengan masyarakat Indonesia. Kesimpulan seminar ini adalah disepakatinya sistem Puskesmas yang terdiri dari Puskesmas tipe A, tipe B, dan C.
Tahun 1968 – Rapat Kerja Kesehatan Nasional, dicetuskan bahwa Puskesmas adalah merupakan sistem pelayanan kesehatan terpadu, yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah (Depkes) menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas disepakati sebagai suatu unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kuratif dan preventif secara terpadu, menyeluruh dan mudah dijangkau, dalam wilayah kerja kecamatan atau sebagian kecamatan di kotamadya/kabupaten.
Tahun 1969 : Sistem Puskesmas disepakati dua saja, yaitu tipe A (dikepalai dokter) dan tipe B (dikelola paramedis). Pada tahun 1969-1974 yang dikenal dengan masa Pelita 1, dimulai program kesehatan Puskesmas di sejumlah kecamatan dari sejumlah Kabupaten di tiap Propinsi.
Tahun 1979 Tidak dibedakan antara Puskesmas A atau B, hanya ada satu tipe Puskesmas saja, yang dikepalai seorang dokter dengan stratifikasi puskesmas ada 3 (sangat baik, rata-rata dan standard). Selanjutnya Puskesmas dilengkapi dengan piranti

manajerial yang lain, yaitu Micro Planning untuk perencanaan, dan Lokakarya Mini (LokMin) untuk pengorganisasian kegiatan dan pengembangan kerjasama tim.
Tahun 1984 Dikembangkan program paket terpadu kesehatan dan keluarga berencana di Puskesmas (KIA, KB, Gizi, Penaggulangan Diare, Immunisasi).
Awal tahun 1990-an Puskesmas menjelma menjadi kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga memberdayakan peran serta masyarakat, selain memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
3. Pelayanan Esensial Tenaga KesmasBerdasarkan Naskah Akademik Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat, terdapat
3 bentuk pelayanan esensial tenaga kesehatan masyarakat, yakni :1) Fungsi Assessment
Pelayanan esensial :a) Monitoring status kesehatan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan di
masyarakat.b) Mendiagnosis dan investigasi masalah kesehatan dan risikonya di masyarakat.c) Mengevaluasi keefektifan, aksebilitas dan terjaminnya pelayan kesehatan
berkualitas.2) Fungsi pengembangan kebijakan kesehatan pelayanan esensial :
a) Mengembangkan kebijakan dan rencana program yang mendukung upaya kesehatan individu dan masyarakat.
b) Mengembangkan kebijakan dan regulasi untuk melindungi dan menjamin kesehatan masyarakat.
c) Penelitian untuk memperoleh wawasa baru dan solusi inovatif untuk masalah kesehatan.
3) Fungsi jaminana) Mengaitkan antara kebutuhan pelayanan personal dan menjamin ketersediaan
pelayanan kesehatan.b) Menjamin keberadaan tenaga kesehatan masyarakat yang kompeten.c) Memberikan informasi, mendidik dan memberdayakan masyarakat terkait isu-
isu kesehatan.d) Mobilisasi masyarakat sebagai partner untuk mengidentifikasi dan memecahkan
masalah kesehatan masyarakat.
4. KompetensiBerdasarkan Naskah Akademik Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat, ada 8 kompetensi utama untuk profesional kesehatan masyarakat yang terdapat pada gambar, diantarannya :

Kompetensi kesmas :1) Mampu melakukan kajian dan analisis situasi (analitic/assessment skills)2) Mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program (policy
development/program planning skills)3) Mampu berkomunikasi secara efektif (communication skills)4) Mampu memahami budaya setempat (cultural competency skills)5) Mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat (comunity empowerment)6) Memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat (public health science skills)7) Mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen
(financial planning and management skills)8) Memiliki kemampuan kepemimpinan dan berfikir sistem (leadership and system
thinking skills).
5. Peran Tenaga Kesehatan Masyarakat1) Peran Tenaga Kesehatan Masyarakat Dalam Pembangunan Kesehatan
Sumber daya manusia kesehatan untuk menjalankan pembangunan kesehatan perlu dikembangkan agar tercipta tatanan yang mengatur produksi, distribusi dan utilisasi SDM kesehatan yang berkualitas, produktif, berdedikasi, bermoral dan beretika yang tersebar secara merata dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan.
Tenaga kesehatan masyarakat (Kesmas) merupakan bagian dari sumber daya manusia, yang sangat penting perannya dalam pembangunan kesehatan dalam sistem kesehatan nasional (SKN). Pembangunan kesehatan dengan paradigma sehat merupakan upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui kesadaran yang lebih tinggi pada pentingnya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Oleh karea itu untuk mewujudkan paradigma sehat tersebut, diperlukan kontribusi yang lebih besar dari para tenaga kesehatan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di Indonesia.
Dalam pelayanan promotif membutuhkan tenaga-tenaga kesmas yang handal terutama yang mempunyai spesialisasi dalam penyuluhan dan pendidikan. Untuk itu perlu dipersiapkan tenaga terlatih di bidang promosi kesehatan termasuk para pakar yang memahami tentang sosiologi, anthropologi, ilmu perilaku, psikologi sosial, ilmu penyuluhan, pakar media penyuluhan dan masih banyak lagi

ilmu yang berhubungan dengan maslaah promosi seperti pemasaran sosial dan lain-lain.
Dalam pelayanan preventif diperlukan para tenaga yang memahami tentang epidemologi penyakit, cara-cara dan metode pencegahan serta pengendalian penyakit. Keterlibatan tenaga kesmas dalam pelayanan preventif di bidang pengendalian memerlukan penguasaan teknik-teknik lingkungan dan pemberantasan penyakit.
2) Peran Tenaga Kesehatan Masyarakat dalam Merubah Perilaku Masyarakat Menuju Hidup Bersih dan Sehat
Program promosi perilaku hidup bersih dan sehat yang biasa dikenal PHBS/promosi higiene merupakan pendekatan terencana untuk mencegah penyakit diare dan penyakit menular yang lain melalui pengadopsian perubahan perilaku oleh masyarakat secara meluas. Program ini dimulai dengan apa yang diketahui, diinginkan dan dilakukan masyarakat setempat dan mengembangkan program berdasarkan informasi tersbeut (Curtis, V dkk, 1997; UNICEF, WHO. Bersih, Sehat dan Sejahtera).
Program promosi PHBS harus dilakukan secara profesional oleh individu dan atau kellompok yang mempunyai kemampuan dan komitmen terhadap kesehatan masyarakat serta memahami tentang lingkungan dan mampu melaksanakan komunikasi, edukasi dan menyampaikan informasi secara tepat dan benar (promosi kesehatan). Tenaga kesmas diharapkan mampu mengambil mengambil bagian dalam promosi PHBS sehingga dapat melakukan perubahan perilaku masyarakat untuk hidup berdasarkan PHBS. Tenaga kesmas telah mempunyai bekal yang cukup untuk dikembangkan dan pada waktunya disumbangkan kepada masyarakat dimana mereka bekerja.
Peran tenaga kesmas dalam pelaksanaan program PHBS, diantaranya (UNICEF, WHO. Bersih, Sehat dan Sejahtera; Fraeff dkk, 1993; Van Wijk dkk, 1995) : (1) memperkenalkan kepada masyarakat tentang gagasan dan teknik mempromosikan perilaku PHBS; (2) mengidentifikasi perilaku masyarakat yang perlu dirubah dan teknik-teknik mengembangkan strategi untuk perubahan perilaku individu, keluarga dan masyarakat. (3) memotivasi perubahan perilaku masyarakat; (4) merancang program komunikasi untuk berbagai kelompok sasaran.
Sasaran promosi PHBS tidak hanya sebatas tentang hygiene, namun mencakup pula perubahan lingkungan fisik, biologi dan sosial-budaya. Perubahan terhadap lingkungan memerlukan intervensi dari para tenaga kesehatan terutama tenaga kesmas yang mempunyai kompetensi sehingga tercipta lingkungan yang kondusif dalam PHBS. Untuk itu tenaga kesmas harus membekali diri dengan belajar secara berkesinambungan sehingga mampu memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan menuju masyarakat sejahtera.
AHLI GIZI

1. DefinisiIlmu gizi Menurut komite Thomas dan Earl (1994) adalah “The nutrition sciences
are the most interdisciplinary of all sciences”. Yang arti bebasnya menyatakan bahwa ilmu gizi merupakan ilmu yang melibatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan.
Menurut Soekirman, (2000), Ilmu Gizi diartikan sebagai Ilmu pengetahuan yang membahas sifat-sifat nutrien yang terkandung dalam makanan, pengaruh metaboliknya serta akibat yang timbul bila terdapat kekurangan-kelebihan zat gizi.
Dalam ilmu gizi terapan, Gizi diartikan sebagai segala sesuatu tentang makanan dan hubungannya dengan kesehatan. Setiap makanan mengandung unsur-unsur gizi (zat gizi). Unsur-unsur gizi ini dikelompokkan atau digolongkan dalam 6 golongan besar yaitu (1) Karbohidrat, (2). Protein, (3).Lemak, (4) Vitamin, (5) Mineral dan (6) air.
2. Sejarah perkembanganPerkembangan Ilmu Gizi. Titik tolak perkembangan ilmu gizi dimulai pada masa
manusia purba dan pada abad pertengahan sampai pada masa munculnya ilmu pengetahuan pada abad ke-19 dan ke-20. Pada masa manusia purba ilmu gizi dinyatakan sebagai suatu evolusi. Disini para peneliti menggambarkan manusia sebagai pemburu makanan dan dikenal sebagai Todhunter, perkembangan ilmu gizi sebagai suatu evolusi.
Bagi manusia purba, fungsi utama dan mungkin fungsi satu-satunya dari makanan adalah untuk mempertahankan hidup. Untuk itu aktifitas utama dari manusia purba adalah mencari makanan dengan berburu. Fungsi utama makanan untuk mempertahankan hidup, meskipun bukan fungsi satu-satunya. Makanan untuk mempertahankan hidup ini juga masih sering atau berlaku bagi sebagian penduduk modern sekarang.
Di abad-abad sebelum masehi filosof Junani bernama Hippocrates (460-377 SM), yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Kedokteran, dalam salah satu tulisannya berspekulasi tentang peran makanan dalam “pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan penyakit” yang menjadi dasar perkembangan ilmu dietetika yang belakangan dikenal dengan “Terapi Diit’
Memasuki abad ke-16 berkembang doktrin bukan saja pemeliharaan kesehatan yang dapat dicapai dengan pengaturan makanan tetapi kemudian berkembang juga tentang hubungan antara makanan dan panjang umur. Misalnya Cornaro, yang hidup lebih dari 100 tahun (1366-1464) dan Francis Bacon (1561-1626) berpendapat bahwa “makan yang diatur dengan baik dapat memperpanjang umur”. Memasuki abad ke-17 dan ke-18, tercatat berbagai penemuan tentang sesuatu yang dimakan (makanan) yang berhubungan dengan kesehatan semakin banyak dan jelas, baik yang bersifat kebetulan maupun yang dirancang yang kemudian mendorong berbagai ahli kesehatan waktu itu untuk melakukan berbagai percobaan.
Pada Abad ke-18 berbagai penemuan ilmiah dimulai, termasuk ilmu-ilmu yang mendasari ilmu gizi. Satu diantaranya yang terpenting adalah penemuan adanya hubungan antara proses pernapasan yaitu proses masuknya O2 ke dalam tubuh dan keluarnya CO2, dengan proses pengolahan makanan dalam tubuh olehAntoine Laurent Lavoisier (1743-1794).
Lavoisier bersama seorang ahli fisika Laplace merintis untuk pertama kalinya penelitian kuantitatif mengenai pernapasan dengan percobaan binatang (kelinci). Oleh

karena itu Lavoisier selain sebagai Bapak Ilmu Kimia, dikalangan ilmuwan gizi dikenal juga sebagai Bapak Ilmu Gizi Dunia.
Penemuan Ilmu-Ilmu yang mendasari terbentuknya Ilmu Gizi itu diantaranya : Tahun 1687 = Penetapan standar makanan. Dimana penetapan ini mengatur
tentang makanan yang baik untuk tubuh dan yang tidak baik untuk tubuh. Dr. lind (1747) menemukan jeruk manis untuk menanggulangi sariawan / scorbut,
belakangan diketahui jeruk manis banyak mengandung vitamin C. Sehingga Vitamin C dikenal juga sebagai pencegah Sariawan/Scorbut.
Suster Florence Nightingale (1854 ) menyimpulkan penderita-penderita akibat perang yang merupakan pasiennya, dalam hal Pemberian makanan kepada pasien harus sesuai dengan kebutuhan pasien untuk mempercepat proses penyembuhannya. Suster Florence Nightingale dikenal juga sebagai Tokoh Keperawatan Dunia.
Liebig (1803-1873) Analisis Protein, KH dan Lemak. Yang merupakan Komponen utama penghasil energi tubuh.
Vait (1831-1908), Rubner (1854-1982), Atwater (1844-1907), Lusk (1866-1932) dikenal sebagai Pakar dalam pengukuran energi dengan kalorimeter. (kkal).
Hopkin (1861-1947), Eljkman (1858-1930) = perintis penemuan vitamin dan membedakannya vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak.
Mendel (1872-1935), Osborn (1859-1929)= penemuan vitamin dan analisis kualitas protein. Memperjelas posisi vitamin dalam makanan dan peranannya dalam tubuh manusia serta kualitas protein yang dilihat dari struktur yaitu asam amino yang essensial maupun yang non essensial.
Pada abad ke 20 Mc Collum, Charles G King = melanjutkan penelitian vitamin kemudian terus berkembang hingga muncul “ SCIENCE of NUTRION. Adalah Suatu cabang ilmu pengetahuan kesehatan (kedokteran) yang berdiri sendiri yaitu Ilmu Gizi adalah Ilmu pengetahuan yang membahas sifat-sifat nutrien yang terkandung dalam makanan, pengaruh metaboliknya serta akibat yang timbul bila terdapat kekurangan zat gizi, ( Soekirman, 2000).
Dalam perkembangan selanjutnya permasalahan gizi mulai bermunculan secara kompleks yang tidak dapat ditanggulangi oleh para ahli gizi dan sarjana gizi saja, sehingga muncul Ilmu gizi yang menurut komite Thomas dan Earl (1994) adalah “The NUTRITION SCIENCES are the most interdisciplinary of all sciences”. Yang arti bebasnya menyatakan bahwa ilmu gizi merupakan ilmu yang melibatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan.
Bagaimana Perkembangan Ilmu Gizi di Indonesia, berikut beberapa hasil penelitian dalam sejarah perkebangan Ilmu Gizi di Indonesia.
Belanda mendirikan “Laboratorium Kesehatan (15-1-1888) di Jakarta. Tujuannya Menanggulangi Penyakit Beri-Beri di Indonesia dan Asia.
Tahun 1934 = Lembaga Makanan Rakyat.

Tahun 1938, bermula dari Tahun 1919, Jansen dan Donath meneliti masalah Gondok di wonosobo, kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda menfaslitasi pembentukan Lembaga Eijkman. Beberapa Kegiatannya berupa survai gizi di tahun 1927-1942, oleh Jansen dan Kawan-kawan pada 7 lokasi bertempat di jawa, seram dan lampung yang bertujuan Mengamati Pola Makan, Keadaan Gizi, Pertanian dan perekonomian. Lembaga ini juga berhasil melakukan Analisis Bahan Makanan yang sekarang dikenal sebagai Daftar Komposisi Bahan Makanan disingkat atau dikenal dengan DKBM.
Tahun 1930, De Hass dkk menemukan defisiensi Vitamin A, (1935) meneliti tentang KEP (Kurang Energi Protein).
Tahun 1950, Lembaga Makanan Rakyat berada dibawah Kementerian Kesehatan RI ( diketuai Prof. Poerwo Soedarmo Pendiri PERSAGI atau dikenal juga sebagai Bapak Gizi Indonesia. Bapak Poerwo Soedarmo juga berhasil memperkenalkan promosi gizi yang baik dengan istilah “Empat Sehat Lima Sempurna” yang begitu populer pada waktu itu sampai pada pemerintahan Orde Baru.
Penelitian-Penelitian di Indonesia ini yang kemudian menarik perhatian WHO dan dijadikan sebagai rekomendasinya adalah :
Domen (1952-1955) penelitian tentang kwashiorkor (istilah gizi buruk karena kekuranagn protein) dan Xeropthalmia (Istilah Kebutaan Akibat kekurangan Vitamin A).
Klerk (1956) penelitian tentang Tinggi Badan (TB) dan Berat Badan (BB) anak Sekolah yang dapat memberikan gambaran Status Gizi Anak SD pada masa balitanya.
Gailey ( 1957 – 1958 ) tentang Kelaparan di Gunung Kidul menghasilkan teori Kelaparan. KELAPARAN (Hunger) menurut E.Kennedy,(2002) sebagai kutipan dari penelitian Prof Soekirman Ph.D Guru Besar Ilmu Gizi IPB Bogor tentang kelaparan adalah Rasa “tidak enak” dan sakit, akibat kurang /tidak makan,baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja diluar kehendak dan terjadi berulang-ulang, serta dalam jangka waktu tertentu menyebabkan penurunan berat badan dan gangguan kesehatan.
Prof. Poerwo Soedarmao Mencetak Tenaga Ahli Gizi ( AKZI dan FKUI) Dan tahun 1950-2010 perkembangan ilmu gizi di Indonesia sangat pesat, sampai
–sampai teori-teori gizi yang baru ditemukan belum sampai diterapkan muncul lagi ilmu yang terbaru dari hasil penelitian terbaru dari ilmu gizi.
Dari Perkembangan Ilmu Gizi tersebut diatas baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, Penjelasan mengenai makanan dan hubungannya dengan kesehatan semakin jelas yaitu makanan atau unsur-unsur (zat-zat) gizi essensial yang tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus dikonsumsi dari makanan meliputi Vitamin, Mineral, Asam amino, Asam lemak Dan sejumlah Karbohidart sebagai energy. Dan unsur-unsur (zat-zat) gizi non essensial dapat disistesis oleh tubuh dari senyawa atau zat gizi tertentu. Unsur-unsur

gizi ini dikelompokkan atau digolongkan dalam 6 golongan besar yaitu (1) Karbohidrat, (2). Protein, (3).Lemak, (4) Vitamin, (5) Mineral dan (6) air.
3. KompetensiUntuk kerja kompetensi nutrisionis dibedakan berdasarkan kata kerja dari 4 tingkatan
yang disusun secara berurutan dan dimulai dari tingkatan untuuk kerja paling rendah. Tingkatan untuk kerja yang lebih tinggi menggambarkan bahwa tingkatan untuk kerja yang lebih rendah dianggap telah mampu dilaksanakan.
a) Membantu : melakukan kegiatan secara independen dibawah pengawasan atau berpatisipasi (berperan serta ) : mengambil bagian kegiatan tim.
b) Melaksanakan : mampu melakukan kegiatan yanpa pengawasan langsung, atau melakukan : mampu melakukan kegiatan secara mandiri.
c) Mendidik : mampu melaksanakan fungsi-fungsi khusus yang nyata; aktivitas yang di delegasikan yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan atau pekerjaan, dll atau menyelia/mengawasi/memantau : pengguna sumber daya, masalah-masalah lingkungan atau mampu mengkoordinasi dan mengarahkan kegiatan dan pekerjaan tim.
d) Mengelola : Mampu merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan suatu organisasi
Standar Kompetensi Peran Ahli Gizi
a) Pelaku tatalaksana/asuhan/pelayanan gizi klinikb) Pengelola pelayanan gizi masyarakatc) Pengelola tatalaksana/asuhan/pelayanan gizi RSd) Pengelola sistem penyelenggaraan makanan instusi masale) Pendidik/penyuluh/pelatih/konsultasi gizif) Pelaksana penelitian gizig) Pelaku pemasaran produk gizi dan kegiatan wirausahah) Berpartisipasi bersama Tim Kes dan Linseki) Pelaku praktek kegizian yang bekerja secara profesional
No Kode Judul Unit Kompetensi
1 Kes.AG.01.01.01 Berpenampilan (Unjuk Kerja) sesuai dengan kode etik profesi gizi.
2 Kes.AG.01.02.01 Merujuk klien/pasien kepada ahli lain pada saat situasinya berada di luar kompetensinya.
3 Kes.AG.01.03.01 Ikut aktif dalam kegiatan kegiatan profesi gizi
4 Kes.AG.01.04.01 Melakukan pengkajian diri menyiapkan portofolio untuk pengembangan profesi dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan

pendidikan berkelanjutan.
5 Kes.AG.01.05.01 Berpartisipasi dalam proses kebijakan legislatif dan kebijakan publik yang berdampak pada pangan, gizi dan pelayanan kesehatan.
6 Kes.AG.01.06.01 Menggunakan teknologi terbaru dalam kegiatan informasi dan komunikasi.
7 Kes.AG.02.07.01 Mendokumentasikan kegiatan pelayanan gizi.
8 Kes.AG.02.08.01 Melakukan pendidikan gizi dalam kegiatan praktek tersupervisi.
9 Kes.AG.02.09.01 Mendidik pasien/klien dalam rangka promosi kesehatan, pencegahan penyakit dan terapi gizi untuk kondisi tanpa komplikasi.
10 Kes.AG.02.10.01 Melaksanakan pendidikan dan pelatihan gizi untuk kelompok sasaran.
11 Kes.AG.02.11.01 Ikut serta dakam pengkajian dan pengembangan bahan pendidikan untuk kelompok sasaran.
12 Kes.AG.02.12.01 Menerapkan pengetahuan dan ketrampilan baru dalam
13 Kes.AG.01.13.01 Ikut serta dalam peningkatan kualitas pelayanan atau praktek dietetik untuk kepuasan konsumen.
14 Kes.AG.01.14.01 Berpartisipasi dalam pengembangan dan pengukuran kinerja dalam pelayanan gizi
15 Kes.AG.01.15.01 Berpatisipasi dalam proses penataan dan pengembangan organisasi
16 Kes.AG.02.16.01 Ikut serta dalam penyusunan rencana operasional dan anggaran institusi.
17 Kes.AG.02.17.01 Berpartisipasi dalam penetapan biaya pelayanan gizi
18 Kes.AG.02.18.01 Ikut serta dalam pemasaran produk pelayanan gizi
19 Kes.AG.01.19.01 Ikut serta dalam pendayagunaan dan pembinaan SDM dalam pelayanan gizi
20 Kes.AG.02.20.01 Ikut serta dalam manajemen sarana dan prasarana pelayanan Gizi
21 Kes.AG.01.21.01 Menyelia sumberdaya dalam unit

pelayanan gizi meliputi keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan pelayanan gizi
22 Kes.AG.02.22.01 Menyelia produksi makanan yang memenuhi kecukupan gizi, biaya dan daya terima
23 Kes.AG.02.23.01 Mengembangkan dan atau memodifikasi resep/formula (mengembangkan dan meningkatkan mutu resep daan makanan formula
24 Kes.AG.02.24.01 Menyusun standar makanan (menerjemahkan kebutuhan gizi ke bahan makanan/menu) untuk kelompok sasaran
25 Kes.AG.02.25.01 Menyusun menu untuk kelompok sasaran
26 Kes.AG.02.26.01 Melakukan uji citarasa/uji organoleptik makanan
27 Kes.AG.02.27.01 Menyelia pengadaan dan distribusi bahan makanan serta transportasi makanan
28 Kes.AG.02.28.01 Mengawasi/menyelia masalah keamanan dan sanitasi dalam penyelenggaraan makanan (industri pangan)
29 Kes.AG.02.29.01 Melakukan penapisan gizi (nutrition screening) pada klien/pasien secara individu
30 Kes.AG.02.30.01 Melakukan pengkajian gizi (nutritional assessment) pasien tanpa komplikasi (dengan kondisi kesehatan umum, misalnya hipertensi, jantung, obesitas)
31 Kes.AG.02.31.01 Membantu dalam pengkajian gizi (nutritional assessment) pada pasien dengan komplikasi (kondisi kesehatan yang kompleks, misalnya penyakit ginjal, multi-sistem organ failure, trauma).
32 Kes.AG.02.32.01 Membantu merencanakan dan mengimplementasikan rencana asuhan gizi pasien
33 Kes.AG.02.33.01 Melakukan monitoring dan evaluasi asupan gizi/makan pasien
34 Kes.AG.02.34.01 Berpartisipasi dalam pemilihan formula enteral serta monitoring dan evaluasi

penyediaannya
35 Kes.AG.02.35.01 Melakukan rencana perubahan diit
36 Kes.AG.01.36.01 Berpartisipasi dalam konferensi tim kesehatan untuk mendiskusikan terapi danrencana pemulangan klien/pasien
37 Kes.AG.01.37.01 Merujuk pasien/klien ke pusat pelayanan kesehatan lain
38 Kes.AG.02.38.01 Melaksanakan penapisan gizi/screening status gizi populasi dan atau kelompok masyarakat
39 Kes.AG.02.39.01 Membantu menilai status gizi populasi dan/atau kelompok masyarakat
40 Kes.AG.02.40.01 Melaksanakan asuhan gizi untuk klien sesuai kebudayaan dan kepercayaan dari berbagai golongan umur (tergantung level asuhan gizi kelompok umur)
41 Kes.AG.01.41.01 Berpartisipasi dalam program promosi kesehatan/pencegahan penyakit di masyarakat
42 Kes.AG.01.42.01 Berpartisipasi dalam pengembangan dan evaluasi program pangan dan gizi di masyarakat
43 Kes.AG.02.43.01 Melaksanakan dan mempertahankan kelangsungan program pangan dan gizi masyarakat
44 Kes.AG.01.44.01 Berpartisipasi dalam penetapan biaya pelayanan gizi.
4. Peran Ahli Gizi dan Ahli Madya GiziAhli Gizi
a. Pelaku tatalaksana/ asuhan /pelayanan gizi klinik b. Pengelola pelayanan gizi dimasyarakat c. Penelol tatalaksana / asuhan / pelayanan gizi di RS d. Pengelola sistem penyelenggaraan makanan Institusi / masal e. Pendidik / penyuluh / pelatih / konsultan gizi f. Pelaksana penelitian gizi g. Pelaku pemasaran produk gizi dan kegiatan wirausaha h. Berpattisipasi bersama tim kesehatan dan tim lintas sektoral i. Pelaku praktik kegizian yang bekerja secara profesional dan etis
Ahli Madya Gizi

a. Pelaku tatalaksana / asuhan / pelayanan gizi klinik b. Pelaksanaa pelayanan gizi masyarakat c. Penyelia sistem penyelenggaraan makanan institusi / masal d. Pendidik / penyuluh / konsultan gizi e. Pelaku pemasaran produk gizi dan kegiatan wirausaha f. Pelaku praktik kegizian yang bekerja secara profesional dan etis
REFERENSI
Thaha, R. M. (2014). Naskah akademik pendidikan tinggi kesehatan masyarakat. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI).
Sukowati, S dan Shinta (n.d.) Peran tenaga kesehatan masyarakat dalam mengubah perilaku masyarakat menuju hidup bersih dan sehat. Media Litbang Kesehatan Volume XIII Nomor 2 Tahun 2003.
Aditama. (2010). Sejarah kesehatan masyarakat. Diakses pada Kamis, 5 Maret 2015 pukul 19.00 WIB dari http://aditama.student.umm.ac.id/2010/08/19/sejarah-kesehatan-masyarakat/
DPP PERSAGI. (n.d.) Standar profesi gizi. PERMENKES 374/2007 dan 26/2013.
Fajar, Ibnu. (n.d.). Standar profesi gizi. SK MENKES 374/III/SK/2007.
Ali, A. R. (2010). Sejarah perkembangan dan ruang lingkup ilmu gizi. Epidemiologi Gizi dan Kesehatan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Indonesia. Diakses pada 9 Maret 2015 pukul 05.13 dari https://arali2008.wordpress.com/2010/10/19/sejarah-perkembangan-ilmu-gizi/
Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya. (n.d.). Kompetensi ahli madya gizi (dasar pendidikan DIII gizi). Diakses pada 9 Maret 2015 pukul 05.15 WIB dari https://arali2008.wordpress.com/2010/10/19/sejarah-perkembangan-ilmu-gizi/
Pakpahan, N. T. (2008). Standar profesi ahli gizi. Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diakses pada 9 Maret 2015 pukul 05.15 WIB dari http://www.hukor.depkes.go.id/?art=24&set=20