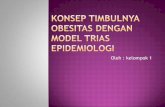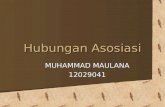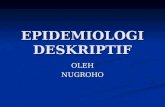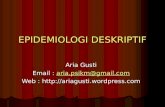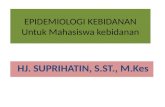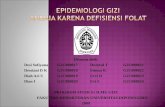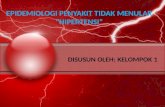PROYEK 05 EPIDEMIOLOGI
Transcript of PROYEK 05 EPIDEMIOLOGI

7/22/2019 PROYEK 05 EPIDEMIOLOGI
http://slidepdf.com/reader/full/proyek-05-epidemiologi 1/16
1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Campak adalah suatu penyakit akut dengan daya penularan tinggi, yang ditandai dengan
demam, korisa, konjungtivitis, batuk disertai enanthem spesifik (Koplik's spot) diikuti ruam
makulopapular menyeluruh. Komplikasi campak cukup serius seperti diare, pneumonia, otitis
media, eksaserbasi dan kematian.(1)
Campak dalam sejarah anak telah dikenal sebagai pembunuh terbesar, meskipun adanya
vaksin telah dikembangkan lebih dari 30 tahun yang lalu, virus campak ini menyerang 50 juta
orang setiap tahun dan menyebabkan lebih dari 1 juta kematian. Insiden terbanyak berhubungan
dengan morbiditas dan mortalitas penyakit campak yaitu pada negara berkembang, meskipun
masih mengenai beberapa negara maju seperti Amerika Serikat.(2)
Sejak tahun 2002, kematian akibat campak di dunia mencapai 777.000. di antaranya
202.000 berasal dari Negara ASEAN. Di Indonesia 30.000 anak meninggal/ tahun akibat
komplikasi campak. artinya tiap 20 menit - 1 anak meninggal. Setiap tahun, lebih dari 1 juta
anak belum terimunisasi campak .(3)
Indonesia adalah Negara keempat terbesar penduduknya di dunia yang memiliki angka
kesakitan campak sekitar 1 juta pertahun dengan 30.000 kematian, yang menyebabkan Indonesia
menjadi salah satu dari 47 negara prioritas yang di identifikasi oleh WHO dan UNICEF untuk
melaksanakan akselerasi dan menjaga kesinambungan dari reduksi campak. Strategi untuk
kegiatan ini adalah cakupan rutin yang tinggi (>90%) di setiap kabupaten/kota serta memastikan
semua anak mendapatkan kesempatan kedua untuk imunisasi campak.(4)

7/22/2019 PROYEK 05 EPIDEMIOLOGI
http://slidepdf.com/reader/full/proyek-05-epidemiologi 2/16
2
1.2 Tujuan
1. Untuk mengetahui pengertian campak.
2. Untuk mengetahui Epidemiologi campak.
3. Untuk mengetahui etiologi dan patologi penyakit campak.
4. Untuk mengetahui gejala klinis dan langkah penegakan diagnosis campak.
5. Untuk mengetahui pengobatan penyakit campak.
6. Untuk mengetahui komplikasi dan prognosis penyakit campak.
7. Untuk mengetahui cara penularan dan pencegahan penyakit campak.

7/22/2019 PROYEK 05 EPIDEMIOLOGI
http://slidepdf.com/reader/full/proyek-05-epidemiologi 3/16
3
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Campak
2.1.1 Definisi
Campak juga dikenal dengan nama morbili atau morbillia dan rubeola (bahasa Latin),
yang kemudian dalam bahasa Jerman disebut dengan nama masern, dalam bahasa Islandia
dikenal dengan nama mislingar dan measles dalam bahasa Inggris.(5) Campak adalah penyakit
infeksi yang sangat menular yang disebabkan oleh virus, dengan gejala-gejala eksantem akut,
demam, kadang kataral selaput lendir dan saluran pernapasan, gejala-gejala mata, kemudian
diikuti erupsi makulopapula yang berwarna merah dan diakhiri dengan deskuamasi dari kulit.
Menurut Pedoman Pengobatan Dasar Puskesmas 2007 campak adalah infeksi virus yang akut
yang bermanifestasi dalam 3 stadium yaitu stadium kataral, erupsi, dan konvalens.(6)
2.1.2 Etiologi
Virus campak berasal dari genus Morbilivirus dan family Paramyxoviridae. Virus
campak liar hanya patogen untuk primata. Kera dapat pula terinfeksi campak lewat darah atau
sekret nasofaring dari manusia. Hopkins, Koplan dan Hinman menyatakan bahwa campak tidak
mempunyai reservoir pada hewan dan tidak menyebabkan karier pada manusia. Virion campak
berbentuk spheris, pleomorphic, dan mempunyai sampul (envelope) dengan diameter 100-250
nm. Virion terdiri dari nukleocapsid yaitu helix dari protein RNA dan sampul yang mempunyai
tonjolan pendek pada permukaannya. Tonjolan pendek ini disebut pepfomer, dan terdiri dari

7/22/2019 PROYEK 05 EPIDEMIOLOGI
http://slidepdf.com/reader/full/proyek-05-epidemiologi 4/16
4
hemaglutinin (H) peplomer yang berbentuk bulat dan fusion (F) peplomer yang berbentuk seperti
bel (dumbbell-shape). Berat molekul dari single stranded RNA adalah 4,5 X 106.(7)
Virus campak terdiri dari 6 protein struktural, 3 tergabung dalam RNA yaitu
nukleoprotein (N), polymerase protein (P), dan large protein (L); 3 protein lainnya berhubungan
dengan sampul virus. Membran sampul terdiri dari M protein (glycosylated protein) yang
berhubungan dengan bagian dalam lipid bilayer dan 2 glikoprotein H dan F. Glikoprotein H
menyebabkan adsorbsi virus pada reseptor host. CD46 yang merupakan complement regulatory
protein dan tersebar luas pada jaringan primata bertindak sebagai reseptor glikoprotein H.
Glikoprotein F menyebabkan fusi virus pada sel host, penetrasi virus dan hemolisis. Dalam
kultur set, virus campak mengakibatkan cytopathic elect yang tcrdiri dari stellate cell dan
multinucleated giant cell. Virus campak ini sangat sensitif pada panas dan dingin, cepat
inaktivasi pada suhu 37°C. Selain itu virus juga menjadi inaktif dengan sinar ultraviolet, ether,
trypsin dan p-propiolactone. Virus tetap infektif pada bentuk droplet di udara selama beberapa
jam terutama pada keadaan dengan tingkat kelembaban yang rendah.(7)
2.1.3 Epidemiologi
Sebagian besar kasus campak menyerang anak-anak. Penularan dapat terjadi melalui
udara yang telah terkontaminasi oleh sekret orang yang telah terinfeksi.
Campak ini juga merupakan penyakit menular yang sering menyebabkan kejadian luar biasa
(KLB). Laporan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT mengalami fluktuasi dalam
periode 5 (lima) tahun dari tahun 2008 – 2012. Pada tahun 2007 kasus campak sebanyak 118
kasus, pada tahun 2008 menurun menjadi 77 kasus selanjutnya mengalami penurunan lagi pada
tahun 2009 menjadi 36 kasus. Pada tahun 2010 meningkat menjadi 170 kasus dan pada tahun
2011 kembali meningkat lagi menjadi 967 kasus dan pada tahun 2012 kembali menurun menjadi

7/22/2019 PROYEK 05 EPIDEMIOLOGI
http://slidepdf.com/reader/full/proyek-05-epidemiologi 5/16
5
114 kasus. Pada tahun 2012 kasus campak ini hanya menyerang 10 Kabupaten/Kota, dengan
jumlah kasus tertinggi di Kab. Rote Ndao sebanyak 35 kasus menyusul Kabupaten Manggarai
Timur sebanyak 20 kasus.(8)
2.1.4 Patofisiologi
Virus campak menginfeksi dengan invasi pads. Epitel traktus respiratorius mulai dari
hidung sampai traktus respiratorius bagian bawah. Multiplikasi local pada mukosa respiratorius
segera disusul dengan viremia pertama dimana virus menyebar dalam leukosit pada system
retikukoendotelial. Setelah terjadi nekrosis pada sel retikuloendotelial sejumlah virus terlepas
kembali dan terjadilah viremia kedua. Sel yang paling banyak terinfeksi adalah monosit. Jaringan
yang terinfeksi termasuk timus, lien, kelenjar limfe, hepar, kulit, konjungtiva dan paru. Setelah
terjadi viremia kedua seluruh mukosa respiratorius terlibat dalam perjalanan penyakit sehingga
menyebabkan timbulnya gejala batuk dan koryza. Campak dapat secara langsung menyebabkan
croup, bronchiolitis dan pneumonia, selain itu adanya kerusakan respiratorius seperti edema dan
hilangnya silia menyebabkan timbulnya komplikasi otitis media dan pneumonia. Setelah
beberapa hari sesudah seluruh mukosa respiratorius terlibat, maka timbullah bercak koplik dan
kemudian timbul ruam pada kulit. Kedua manifestasi ini pada pemeriksaan mikroskopik
menunjukkan multinucleated giant cells, edema inter dan intraseluler, parakeratosis dan
dyskeratosis. Timbulnya ruam pada campak bersamaan dengan timbulnya antibodi serum dan
penyakit menjadi tidak infeksius. Oleh sebab itu dikatakan bahwa timbulnya ruam akibat reaksi
hipersensitivitas host pada virus campak. Hal ini berarti bahwa timbulnya ruam ini lebih ke arah
imunitas seluler. Pernyataaan ini didukung data bahwa pasien dengan defisiensi imunitas seluler
yang terkena campak tidak didapatkan adanya ruam makulopapuler, sedangkan pasien dengan
agamaglobulinemia bila terkena campak masih didapatkan ruam makulopapuler.(7)

7/22/2019 PROYEK 05 EPIDEMIOLOGI
http://slidepdf.com/reader/full/proyek-05-epidemiologi 6/16
6
2.1.5 Gejala Klinis
Secara garis besar penyakit campak dibagi menjadi 3 fase:
1. Fase pertama disebut masa inkubasi yang berlangsung sekitar 10 – 12 hari. Pada fase
ini anak sudah mulai terkena infeksi tapi pada dirinya belum tampak gejala apapun.
Bercak-bercak merah yang merupakan ciri khas campak belum keluar.
2. Pada fase kedua (fase prodormal) barulah timbul gejala yang mirip penyakit flu
seperti batuk, pilek dan demam. Mata tampak kemerah-merahan dan berair. Bila
melihat sesuatu, mata akan silau (fotofobia). Di sebelah dalam mulut muncul bintik-
bintik putih yang akan bertahan 3 – 4 hari. Terkadang anak juga mengalami diare. 1 –
2 hari kemudian timbul demam tinggi yang turun naik, berkisar 38 – 40,5 oC
3. Fase ketiga ditandai dengan keluarnya bercak merah seiring dengan demam tinggi
yang terjadi. Namun bercak tak langsung muncul di seluruh tubuh melainkan
bertahap dan merambat. Bermula dari belakang telinga, leher, dada, muka, tangan dan
kaki. Warnanya pun khas; merah dengan ukuran yang tidak terlalu besar tapi juga
tidak terlalu kecil.
Penyakit campak terdiri dari 3 stadium, yaitu: (9)
1. Stadium kataral (prodormal)
Biasanya stadium ini berlangsung selama 4-5 hari dengan gejala demam, malaise,
batuk, fotofobia, konjungtivitis dan koriza. Menjelang akhir stadium kataral dan 24
jam sebelum timbul eksantema, timbul bercak Koplik. Bercak Koplik berwarna putih
kelabu, sebesar ujung jarum timbul dan dikelilingi oleh eritema, pertama kali muncul
pada mukosa bukal yang menghadap gigi molar dan menjelang kira-kira hari ke 3
atau 4 dari masa prodormal dapat meluas sampai seluruh mukosa mulut. Secara

7/22/2019 PROYEK 05 EPIDEMIOLOGI
http://slidepdf.com/reader/full/proyek-05-epidemiologi 7/16
7
klinis, gambaran penyakit menyerupai influenza dan sering didiagnosis sebagai
influenza.
2. Stadium erupsi
Stadium ini berlangsung selama 4-7 hari. Gejala yang biasanya terjadi adalah koriza
dan batuk-batuk bertambah. Timbul eksantema atau titik merah di palatum durum dan
palatum mole. Kadang terlihat pula bercak Koplik. Terjadinya ruam atau eritema
yang berbentuk makula-papula disertai naiknya suhu badan. Mula-mula eritema
timbul di belakang telinga, di bagian atas tengkuk, sepanjang rambut dan bagian
belakang bawah. Kadang-kadang terdapat perdarahan ringan pada kulit. Rasa gatal,
muka bengkak. Ruam kemudian akan menyebar ke dada dan abdomen dan akhirnya
mencapai anggota bagian bawah pada hari ketiga dan akan menghilang dengan urutan
seperti terjadinya yang berakhir dalam 2-3 hari. Terdapat pembesaran kelenjar getah
bening di sudut mandibula dan di daerah leher belakang. Terdapat pula sedikit
splenomegali. Variasinya disebut “black measles” yaitu morbili yang disertai
perdarahan pada kulit, mulut, hidung dan traktus digestivus.
3. Stadium konvalesensi
Erupsi berkurang meninggalkan bekas yang berwarna lebih tua (hiperpigmentasi)
yang lama-kelamaan akan menghilang sendiri. Selain hiperpigmentasi pada anak
Indonesia sering ditemukan pula kulit yang bersisik. Selanjutnya suhu menurun
sampai menjadi normal kecuali bila ada komplikasi.
2.1.6 Diagnosis banding
2.1.7 Penegakan Diagnosis

7/22/2019 PROYEK 05 EPIDEMIOLOGI
http://slidepdf.com/reader/full/proyek-05-epidemiologi 8/16
8
2.1.8 Pengobatan
2.1.9 Komplikasi
Pada penderita campak dapat terjadi komplikasi yang terjadi sebagai akibat replikasi
virus atau karena superinfeksi bakteri antara lain. (9)(10)
1. Otitis Media Akut
Dapat terjadi karena infeksi bakterial sekunder.
2. Ensefalitis
Dapat terjadi sebagai komplikasi pada anak yang sedang menderita campak atau
dalam satu bulan setelah mendapat imunisasi dengan vaksin virus campak hidup,
pada penderita yang sedang mendapat pengobatan imunosupresif dan sebagai
Subacute sclerosing panencephalitis (SSPE). Angka kejadian ensefalitis setelah
infeksi campak adalah 1 : 1.000 kasus, sedangkan ensefalitis setelah vaksinasi dengan
virus campak hidup adalah 1,16 tiap 1.000.000 dosis.
SSPE jarang terjadi hanya sekitar 1 per 100.000 dan terjadi beberapa tahun setelah
infeksi dimana lebih dari 50% kasus-kasus SSPE pernah menderita campak pada 2
tahun pertama umur kehidupan. Penyebabnya tidak jelas tetapi ada bukti-bukti bahwa
virus campak memegang peranan dalam patogenesisnya. SSPE yang terjadi setelah
vaksinasi campak didapatkan kira-kira 3 tahun kemudian.
3. Bronkopneumonia
Dapat disebabkan oleh virus morbilia atau oleh Pneuomococcus, Streptococcus,
Staphylococcus. Bronkopneumonia ini dapat menyebabkan kematian bayi yang masih
muda, anak dengan malnutrisi energi protein, penderita penyakit menahun misalnya
tuberkulosis, leukemia dan lain-lain.

7/22/2019 PROYEK 05 EPIDEMIOLOGI
http://slidepdf.com/reader/full/proyek-05-epidemiologi 9/16
9
4. Kebutaan
Terjadi karena virus campak mempercepat episode defisiensi vitamin A yang
akhirnya dapat menyebabkan xeropthalmia atau kebutaan.
2.1.10 Prognosis
BAB 3
PEMBAHASAN DAN DISKUSI
3.1 Pencegahan (5 level of prevention against disease)
3.1.1 Pencegahan Primer
a. Promosi Kesehatan
Pencegahan tingkat awal berhubungan dengan keadaan penyakit yang masih dalam tahap
prepatogenesisatau penyakit yang belum tampak yang dapat dilakukan dengan memantapkan
status kesehatan balita dengan memberikan makanan bergizi sehingga dapat meningkatkan daya
tahan tubuh.
1. Memberi penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan imunisasi
campak untuk semua bayi.
2. Imnunisasi dengan virus campak hidup yang dilemahkan, yang diberikan pada semua
anak berumur 9 bulan sangat dianjurkan karena dapat melindungi sampai jangka waktu 4-
5 tahun.
b. Perlindungan umum dan spesifik

7/22/2019 PROYEK 05 EPIDEMIOLOGI
http://slidepdf.com/reader/full/proyek-05-epidemiologi 10/16
10
Pencegahan ini dilakukan dalam mencegah munculnya factor predisposisi/ resiko terhadap
penyakit Campak. Sasaran dari pencegahan primordial adalah anak-anak yang masih sehat dan
belum memiliki resiko yang tinggi agar tidak memiliki faktor resiko yang tinggi untuk penyakit
Campak.
1. Penyuluhan
Edukasi Campak adalah pendidikan dan latihan mengenai pengetahuan mengenai
Campak. Disamping kepada penderita Campak, edukasi juga diberikan kepada anggota
keluarganya, kelompok masyarakat beresiko tinggi dan pihak-pihak perencana kebijakan
kesehatan. Berbagai materi yang perlu diberikan kepada pasien campak adalah definisi
penyakit Campak, faktor-faktor yang berpengaruh pada timbulnya campak dan upaya-
upaya menekan campak, konselling nutrisi dan penataan rumah yang baik, pengelolaan
Campak secara umum, pencegahan dan pengenalan komplikasi Campak.
2. Imunisasi
Di Indonesia sampai saat ini pencegahan penyakit campak dilakukan dengan vaksinasi
Campak secara rutin yaitu diberikan pada bayi berumur 9 – 15 bulan. Vaksin yang
digunakan adalah Schwarz vaccine yaitu vaksin hidup yang dioleh menjadi lemah.
Vaksin ini diberikan secara subkutan sebanyak 0,5 ml. vaksin campak tidak boleh
diberikan pada wanita hamil, anak dengan TBC yang tidak diobati, penderita leukemia.
Vaksin Campak dapat diberikan sebagai vaksin monovalen atau polivalen yaitu vaksin
measles-mumps-rubella (MMR). vaksin monovalen diberikan pada bayi usia 9 bulan,
sedangkan vaksin polivalen diberikan pada anak usia 15 bulan. Penting diperhatikan
penyimpanan dan transportasi vaksin harus pada temperature antara 2ºC - 8ºC atau ± 4ºC,

7/22/2019 PROYEK 05 EPIDEMIOLOGI
http://slidepdf.com/reader/full/proyek-05-epidemiologi 11/16
11
vaksin tersebut harus dihindarkan dari sinar matahari. Mudah rusak oleh zat pengawet
atau bahan kimia dan setelah dibuka hanya tahan 4 jam.
Dimana imunisasi ini terbagi atas 2 yaitu:
a. Imunisasi aktif
Pencegahan campak dilakukan dengan pemberian imunisasi aktif pada bayi
berumur 9 bulan atau lebih. Pada tahun 1963 telah dibuat dua macam vaksin
campak, yaitu (1) vaksin yang berasal dari virus campak hidup yang
dilemahkan (tipe Edmonstone B), dan (2) vaksin yang berasal dari virus campak
yang dimatikan (dalam larutan formalin dicampur dengan garam alumunium).
Namun sejak tahun 1967, vaksin yang berasal dari virus campak yang telah
dimatikan tidak digunakan lagi, oleh karena efek proteksinya hanya bersifat
sementara dan dapat menimbulkan gejala atypical measles yang hebat. Vaksin
yang berasal dari virus campak yang dilemahkan berkembang dari Edmonstone
strain menjadi strain Schwarz (1965) dan kemudian menjadi strais Moraten (1968).
Dosis baku minimal pemberian vaksin campak yang dilemahkan adalah 0,5 ml,
secara subkutan,namun dilaporkan bahwa pemberian secara intramuskular
mempunyai efektivitas yang sama. Vaksin ini biasanya diberikan dalam bentuk
kombinasi denganondongan dan campak Jerman (vaksin MMR/mumps, measles,
rubella), disuntikkan pada otot paha atau lengan atas. Jika hanya mengandung
campak vaksin diberikan pada umur 9 bulan. Dalam bentuk MMR, dosis pertama
diberikan pada usia 12-15 bulan, dosis kedua diberikan pada usia 4-6 tahun.
Vaksin campak sering dipakai bersama-sama dengan vaksin rubela dan parotitis
epidemika yang dilemahkan, vaksin polio oral, difteri-tetanus-polio vaksin dan lain-

7/22/2019 PROYEK 05 EPIDEMIOLOGI
http://slidepdf.com/reader/full/proyek-05-epidemiologi 12/16
12
lain. Laporan beberapa peneliti menyatakan bahwa kombinasi tersebut pada
umumnya aman dan tetap efektif.
b. Imunisasi pasif
Imunisasi pasif dengan kumpulan serum orang dewasa, kumpulan serum konvalesens,
globulin plasenta atau gamma globulin kumpulan plasma adalah efektif untuk
pencegahan dan pelemahan campak. Campak dapat dicegah dengan Immune serum
globulin (gamma globulin) dengan dosis 0,25 ml/kgBB intramuskuler, maksimal 15
ml dalam waktu 5 hari sesudah terpapar, atau sesegera mungkin. Perlindungan yang
sempurna diindikasikan untuk bayi, anak-anak dengan penyakit kronis, dan para
kontak di bangsal rumah sakit serta institusi penampungan anak. Setelah hari ke 7-8
dari masa inkubasi, maka jumlah antibodi yang diberikan harus ditingkatkan untuk
mendapatkan derajat perlindungan yang diharapkan.Kontraindikasi vaksin : reaksi
anafilaksis terhadap neomisin atau gelatin, kehamilan imunodefisiensi (keganasan
hematologi atau tumor padat, imunodefisiensi kongenital, terapi imunosupresan
jangka panjang, infeksi HIV dengan imunosupresi berat.
c. Isolasi
Penderita rentan menghindari kontak dengan seseorang yang terkena penyakit
campak dalam kurun waktu 20-30 hari, demikian pula bagi penderita campak untuk
diisolasi selama 20-30 hari guna menghindari penularan lingkungan sekitar.
3.1.2 Pencegahan Sekunder
a. Diagnosis awal dan perawatan tepat waktu
Pencegahan sekunder adalah upaya untuk mencegah atau menghambat timbulnya
komplikasi dengan tindakan-tindakan seperti tes penyaringan yang ditujukan untuk

7/22/2019 PROYEK 05 EPIDEMIOLOGI
http://slidepdf.com/reader/full/proyek-05-epidemiologi 13/16
13
pendeteksian dini campak serta penanganan segera dan efektif. Tujuan utama kegiatan-
kegiatan pencegahan sekunder adalah untuk mengidentifikasi orang-orang tanpa gejala yang
telah sakit atau penderita yang beresiko tinggi untuk mengembangkan atau memperparah
penyakit. Memberikan pengobatan penyakit sejak awal sedapat mungkin dilakukan untuk
mencegah kemungkinan terjadinya komplikasi. Edukasi dan pengelolaan campak memegang
peran penting untuk meningkatkan kepatuhan pasien berobat.
a. Menentukan diagnosis campak dengan benar baik melalui pemeriksaan fisik atau darah
b. Mencegah perluasan infeksi Anak yang menderita campak jangan masuk sekolah selama
4 hari setelah timbulnya rash. Menempatkan anak pada ruang khusus atau
mempertahankan isolasi di rumah sakit dengan melakukan pemisahan penderita pada
stadium kataral yakni dari hari pertama hingga hari keempat setelah timbulnya rash yang
dapat mengurangi keterpajanan pasien-pasien dengan resiko tinggi lainnya.
c. Pengobatan simtomatik diberikan untuk mengurangi keluhan penderita yakni antipiretik
untuk menurunkan panas dan juga obat batuk. Antibiotika hanya diberikan bila terjadi
infeksi sekunder untuk mencegah komplikasi.
d. Diet dengan gizi tinggi kalori dan tinggi protein bertujuan untuk meningkatkan daya
tahan tubuh penderita sehingga dapat mengurangi terjadinya komplikasi campak yakni
bronkhitis, otitis media, pneumonia, enselefalomieletis, abortus dan miokarditis yang
resivebel.
3.1.3 Pencegahan Tersier
a. Pembatasan ketidakmampuan

7/22/2019 PROYEK 05 EPIDEMIOLOGI
http://slidepdf.com/reader/full/proyek-05-epidemiologi 14/16
14
Pencegahan tersier adalah semua upaya untuk mencegah kecacatan akibat komplikasi.
Kegiatan yang dilakukan antara lain mencegah perubahan dari komplikasi menjadi kecatatan
tubuh dan melakukan rehabilitasi sedini mungkin bagi penderita yang mengalami kecacatan.
Dalam upaya ini diperlukan kerjasama yang baik antara pasien-pasien dengan dokter maupun
antara dokter-dokter yang terkait dengan komplikasinya. Penyuluhan juga sangat dibutuhkan
untuk meningkatkan motivasi pasien untuk mengendalikan penyakit campak. Dalam
penyuluhan ini hal yang dilakukan adalah :
1. Maksud, tujuan, dan cara pengobatan komplikasi kronik
2. Pemberian vitamin A dosis tinggi karena cadangan vitamin A akan turun secara cepar
terutama pada anak kurang gizi yang akan menurunkan imunitas mereka.
3. Kesabaran dan ketakwaan untuk dapat menerima dan memanfaatkan keadaan
hidup dengan komplikasi kronik.
4. Pelayanan kesehatan yang holistik dan terintegrasi antar disiplin terkait juga sangat
diperlukan, terutama di rumah sakit rujukan, baik dengan para ahli sesama ilmu.
b. Rehabilitasi
BAB 4
PENUTUP
4.1Kesimpulan
1. Campak adalah suatu penyakit akut dengan daya penularan tinggi yang disebabkan oleh virus
campak, dari genus Morbilivirus dan family Paramyxoviridae.
2. Sebagian besar kasus campak menyerang anak – anak dan menular melalui udara yang telah
terkontaminasi oleh sekret orang yang telah terinfeksi.

7/22/2019 PROYEK 05 EPIDEMIOLOGI
http://slidepdf.com/reader/full/proyek-05-epidemiologi 15/16
15
3. Di Indonesia 30.000 anak meninggal / tahun akibat komplikasi campak. Setiap tahun lebih dari 1
juta anak belum terimunisasi campak. Di NTT campak juga merupakn penyakit menular yang
sering menyebabkan KLB dan saat ini Kasus tertinggi Di kabupaten Rote Ndao
4. Penyakit campat terdiri dari 3 staduim yaitu stadium kataral/ prodormal, stadium erupsi, dan
stadium konvalesensi
5. Pengobatan :
6. Kpada penderita campak dapat terjadi komplikasi sebagai akibat replikasi virus atau karena
superinfeksi bakteri.
7. Prognosis :
8. Penyakit campak dapat dicegah dengan “ 5 level of prevention against disease “ yaitu
pencegahan primer ( promosi kesehatan, perlindungan umum dan spesifik), pencegahan
sekunder ( diagnosis awal dan perawatan tepat waktu), dan pencegahan tersier ( pembatasan
ketidakmampuan, dan rehabilitasi )
4.2 Saran
Daftar Pustaka
1. Chin. Manual Pemberantasan Penyakit Menular. Atlanta, USA: Centres For DiseaseControl and Prevention; 2000.
2. Burnett M. Measles, Rubeola [Internet]. 2007. Available from: http://www.e-emedicine.com
3. Departemen Kesehatan RI. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia; 2007.
4. Departemen Kesehatan RI. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia; 2009.
5. Sepianessi E. Campak [Internet]. Available from:
http://epidemiologiunsri.blogspot.com/2011/11/campak.html
6. Pedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas. Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
2007.

7/22/2019 PROYEK 05 EPIDEMIOLOGI
http://slidepdf.com/reader/full/proyek-05-epidemiologi 16/16
16
7. Tommy D. Campak. Surabaya: Fakultas Kedokteran UNAIR; 2000.
8. Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012. Dinas kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur; 2012.
9. Staf Pengajar Ilmu Kesehatan Anak FKUI. Ilmu Kesehatan Anak. Buku Kulia. Hassan dr.R, Alatas dr. H, Latief dr. A, Napitupulu dr. PM, Pudjiadi dr. A, Ghazali dr. MV, et al.,
editors. Jakarta: Bagian Ilmu Kesehatan Anak; 1985.
10. Departemen Kesehatan RI. Petunjuk Teknis Kampanye Penyakit Campak. Subdit
Imunisasi Direktorat Epim & Kesma, Direktorat Jenderal PP & PL Departemen KesehatanRI; 2006.