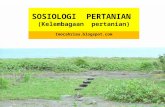pertanian
description
Transcript of pertanian
dianggap penting, hal ini terlihat dari: peranan sektor pertanian terhadap penyediaan lapangan kerja, penyediaan pangan, penyumbang devisa Negara melalui ekspor dan sebagainya
Di tengah kecemasan bahaya pestisida dan pencemaran lingkungan, sistem budidaya tanaman secara organic merupakan salah satu solusinya.
kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sektor pertanian mempunyai efek pengganda kedepan dan kebelakang yang besar, melalui keterkaitan input-output-outcome antar industri, konsumsi dan investasi. Hal ini terjadi secara nasional maupun regional karena keunggulan komparatif sebagian besar wilayah Indonesia adalah di sektor pertanian. Namun demikian kinerja sektor pertanian cenderung menurun akibat kurang mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Pembangunan di masa lalu kurang memperhatikan keunggulan komparatif yang dimiliki. Keunggulan komparatif yang dimiliki belum didayagunakan sehingga menjadi keunggulan kompetitif nasional. Akibat dari strategi yang dibangun tersebut maka struktur ekonomi menjadi rapuh. Krisis ekonomi yang lalu memberi pelajaran berharga dari kondisi tersebut. Apabila pengembangan ekonomi daerah dan nasional didasarkan atas keunggulan yang kita miliki maka perekonomian yang terbangun akan memiliki kemampuan bersaing dan berdayaguna bagi seluruh rakyat Indonesia.Belajar dari pengalaman tersebut, sudah selayaknya strategi pembangunan nasional kembali memperhatikan keunggulan yang dimiliki Indonesia. Untuk itu Kabinet Indonesia Bersatu menetapkan Revitalisaisi Pertanian sebagai salah satu strategi utama pembangunan nasional 2005-2009.Posisi Pertanian Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia Masa DepanPosisi pertanian akan sangat strategis apabila kita mampu mengubah pola pikir masyarakat yang cenderung memandang pertanian hanya sebagai penghasil (output) komoditas menjadi pola pikir yang melihat multi-fungsi dari pertanian. Multi-fungsi pertanian meliputi peran sebagai:a. Penghasil pangan dan bahan baku industri.Sektor pertanian sangat menentukan dalam ketahanan pangan nasional sekaligus menentukan ketahanan bangsa. Penduduk Indonesia tahun 2025 akan mencapai 300 juta lebih, ketahanan nasional akan terancam bila pasokan pangan kita sangat tergantung dari impor. Dalam proses industrialisasi pertanian juga memproduksi bahan baku industri pertanian seperti sawit, karet, gula, serat, dan lainnya.b. Pembangunan daerah dan perdesaan.Pembangunan nasionalakan timpang kalau daerah/perdesaan tidak dibangun, urbanisasi tidak akan bisa ditekan, dan pada akhirnya senjang desa dan kota semakin melebar. Lebih dari 83 persen kabupaten/kota di Indonesia ekonominya berbasis kepada pertanian. Agroindustri perdesaan akan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi perdesaan terutama dalam penyerapan tenaga kerja.
c. Penyangga dalam masa krisis.Sektor pertanian yang berbasis sumberdaya lokal terbukti sangat handal dalam masa krisis ekonomi, bahkan mampu menampung 5 juta tenaga kerja limpahan dari sektor industri dan jasa yang terkena krisis; terselamatkan oleh sektor pertanian.d. Penghubung sosial ekonomi antar masyarakat dari berbagai pulau dan daerah sebagai perekat persatuan bangsa.Masing-masing pulau/daerah memiliki keunggulan komparatif yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan keunggulan masing-masing.Perdagangan (trade)Antar pulau ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi dengan melakukan spesialasisasi masing-masing daerah. Saling ketergantungan antara daerah menjadi jaminan pengembangan ekonomi daerah dan mempererat persatuan antar daerah.e. Kelestarian sumberdaya lingkungan.Kegiatan pertanian berperan dalam penyagga, penyedia air, udara bersih, dan keindahan. Pada haketnya pertanian selalu menyatu denganalam. Membangun pertanian yang berkelanjutan (sustainable) berarti juga memelihara sumberdaya lingkungan. Agrowisata merupakan contoh yang ideal dalam multi-fungsi pertanian.f. Sosial budaya masyarakat Usaha pertanian berkaitan erat dengan sosial-budaya dan adat istiadat masyarakat.Sistemsosial yang terbangun dalam masyarakat pertanian telah berperan dalam membangun ketahanan pangan dan ketahanan sosial, seperti lumbung pangan, sistem arisan dan lainnya.g. Kesempatan kerja, PDB, dan devisa.Lebih dari 25,5 juta keluarga atau 100 juta lebih penduduk Indonesia hidupnya tergantung pertanian. Sektor pertanian menyerap 46,3%tenaga kerja dari total angkatan kerja, menyumbang 6,9% dari total ekspor non migas, dan memberikan kontribusi sebesar 15 persen PDB nasional.Arah Masa Depan Kondisi Petani IndonesiaTransformasi struktur perekonomian yang terjadi menunjukkan bahwa peran pertanian dalam pembangunan nasional terus menurun, namun tidak diikuti oleh bebannya dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini berakibat produktivitas pertanian menurun dan semakin senjang dibanding sektor diluar pertanian, terutama sektor jasa dan industri . Indikator tersebut tercermin dari produktivitas pertanian. Dalam tahun 1993-2003 jumlah petani gurem (dengan luas garapan kurang dari 0,5 ha) meningkat dari 10,8 juta KK menjadi 13,7 juta KK (meningkat 2,6% per tahun). Hal ini menunjukkan terjadinya marjinalisasi pertanian sebagai akibat langsung dari kepadatan penduduk. Sementara itu luas lahan semakin berkurang dan perkembangan kesempatan kerja di luar pertanian terbatas. Jumlah rumah tangga petani (RTP) menurut Sensus Pertanian (SP) 2003 mencapai 25,58 juta RTP. Sekitar 40 persen RTP tergolong tidak mampu dan 20 persen diantaranya dikepalai oleh perempuan. Pada daerah dimana tingkat migrasi tenaga kerja laki-laki tinggi, beban kerja sektor pertanian bergeser kepada tenaga kerja perempuan dan kelompok lanjut usia.Pada bagian lain kualitas SDM pertanian juga rendah. Menurut data BPS tahun 2002, tingkat pendidikan tenaga kerja pertanian yang tidak sekolah dan tidak tamat SD sebesar 35 persen, tamat SD 46 persen, dan tamat SLTP 13 persen. Dibandingkan dengan sektor non pertanian pada tahun yang sama, tingkat pendidikan tenaga kerja yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD 31 persen, tamat SLTP sekitar 20 persen, dan tamat SLTA 27 persen.Tingginya tingkat pendidikan di sektor non pertanian ini sebagian besar berasal dari mereka yang melakukan urbanisasi atau yang meninggalkan sektor pertanian di perdesaan. Dilihat dari karakter komoditas dan jenis usaha yang dilakukan oleh petani, kegureman tidak selalu identik dengan luas penguasaan lahan. Kegureman petani secara umum terkait dengan keterbatasan akses mereka terhadap berbagai sumberdaya pertanian (lahan, air, informasi, teknologi, pasar, modal, dll). Sejalan dengan itu peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani dapat dilakukan melalui:a) peningkatan skala usaha sesuai dengan sifat komoditasnya. Misalnya untuk petani pangan luas lahan minimal 1 hektar per petani di Jawa-Bali dan 2,5 hektar per petani di luar Jawa-Balib) pengusahaan komoditas sesuai dengan permintaan pasarc) diversifikasi usaha rumahtangga melalui pengembangan agroindustri perdesaan dengan kegiatan non-pertaniand) pengembangan kelembagaan penguasaan saham petani untuk sektor hulu maupun hilire) kebijakan perlindungan bagi petani dan usahanya.
Arah Masa Depan Kondisi Sumberdaya Pertanian IndonesiaSumberdaya utama dalam pembangunan pertanian adalah lahan dan air. Akses sektor pertanian terhadap sumber daya tersebut dihadapkan kepada berbagai masalah, seperti:a) terbatasnya sumberdaya lahan dan air yang digunakan,b) sempitnya luas lahan pertanian per kapita penduduk Indonesia (900 m2/kapita),c) banyaknya petani gurem dengan luas lahan garapan perkeluarga petani kurang dari 0,5 ha, (d) tingginya angka konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian dan tidak terjaminnya status penguasaan lahan (land tenure).Sumberdaya lahan yang dipergunakan untuk produksi pertanian relatif terbatas. Dalam dekade terakhir luas lahan pertanian sekitar 17,19 persen dari total lahan, yang terdiri dari 4,08 persen untuk areal perkebunan; 4,07 persen untuk lahan sawah; 2,83 persen untuk pertanian lahan kering dan 6,21 persen untuk lading berpindah. Tingkat pemanfaatan lahan sangat bervariasi antar daerah. Perkembangan luas lahan pertanian, terutama lahan sawah dan lahan kering (tegalan), sangat lambat, kecuali dibidang perkebunan terutama untuk kelapa sawit.Peningkatan jumlah penduduk tahun 2000-2003 sekitar 1,5 persen per tahun menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan terhadap sumberdaya lahan dan air. Luas rata-rata kepemilikan lahan sawah di Jawa dan Bali hanya 0,34 ha per rumah tangga petani. Secara nasional jumlah petani gurem (petani dengan luas lahan garapan < 0,5 ha) meningkat dari 10,8 juta pada tahun 1993 menjadi 13,7 juta rumah tangga petani pada tahun 2003 dengan rata-rata peningkatan jumlah petani gurem sekitar 2,4 persen per tahun.Konversi lahan pertanian terutama terjadi pada lahan sawah yangberproduktivitas tinggi menjadi lahan permukiman dan industri. Hal ini disebabkan karena pada umumnya lahan sawah dengan produktivitas tinggi, seperti di jalur pantai utara Pulau Jawa dan di sekitar Bandung, mempunyai prasarana yang memadai untuk pembangunan sektor non pertanian. Konversi lahan sawah menjadi lahan non-pertanian dari tahun 1999-2002 mencapai 330.000 ha atau setara dengan 110.000 ha/tahun. Luas baku lahan sawah juga cenderung menurun. Antara tahun 1981-1999,neraca pertambahan lahan sawah seluas 1,6 juta ha. Namun antara tahun 1999 sampai 2002 terjadi penciutan luas lahan sawah seluas 0,4 juta ha karena tingginya angka konversiDi sisi lain, fakta menunjukkan bahwa terdapat sekitar 9 juta ha lahan terlantar yang dewasa ini ditutupi semak belukar dan alang-alang. Pemanfaatan lahan yang berpotensi ini secara bertahap akan dapat mengantarkan Indonesia tidak saja berswasembada produk pertanian, tetapi juga berpotensi untuk meningkatkan volume ekspor, apalagi jika insentif untuk petani dapat ditingkatkan. Di samping itu, sekitar 32 juta ha lahan, terutama di luar Pulau Jawa, sesuai dan berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem.Seperti halnya sumberdaya lahan, sumberdaya air juga semakin terbatas dan mengalami degradasi. Pertumbuhan penduduk dan industrialisasi telah menimbulkan kompetisi penggunaan antara pertanian dan non-pertanian. Pada kondisi demikian maka penggunanan air untuk pertanian selalu dikorbankan sebagai prioritas terakhir.Pada bagian lain dalam dekade terkhir perhatian untuk memelihara jaringan irigasi bagi mempertahankan efisiensi penggunaan air juga menurun yang berakibat kepada penurunan intensitas tanam dan produktifitas pertanian. Untuk itu peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi merupakan langkah bagi peningkatan produktifitas pertanian.Untuk itu, dalam rangka revitalisasi pertanian, pengembangan lahan pertanian dapat ditempuh melalui: (i) reformasi keagrariaan untuk meningkatkan akses petani terhadap lahan dan air serta meningkatkan rasio luas lahan per kapita, (ii) pengendalian konversi lahan pertanian dan pencadangan lahan abadi untuk pertanian sekitar 15 juta ha, (iii) fasilitasi terhadap pemanfaatanlahan (pembukaan lahan pertanian baru), serta (iv) penciptaan suasana yang kondusif untuk agroindustri pedesaan sebagai penyedia lapangan kerja dan peluang peningkatan pendapatanserta kesejahteraan keluarga petani
Arah Masa Depan Produk dan Bisnis PertanianDalam kurun waktu yang panjang pembangunan pertanian selalu diidentikkan dengan kegiatan produksi usahatani semata (proses budidaya atau agronomi), sehingga hasil pertanian identik dengan komoditas primer. Kegiatan pertanian masa lalu lebih berorientasi kepada peningkatan produksi komoditas primer dan kurang memberi kesempatan untuk memikirkan pengembangan produk hilir. Dari sisi kebijakan, pembangunan pertanian cenderung terlepas dari pembangunan sektor lain, kebijakan di bidang pertanian tidak selalu diikuti oleh kebijakan pendukung lain secara sinergis.Pembinaan pembangunan pertanian tersekat-sekat oleh banyak institusi, sehingga kebijakan sering tidak sinkron antar lembaga terkait akibat perbedaan kepentingan dari masing-masing sektor. Selama ini kontribusi sektor pertanian terhadap penerimaan devisa lebih banyak diperoleh dari produk segar (primer) yang relative memberi nilai tambah kecil dan belum mengandalkan produk olahan (hilir) yang dapat memberikan nilai tambah lebih besar, walaupun pada akhir-akhir ini ekspor produk olahan telah semakin besar. Dengan mengespor produk primer, maka nilai tambah yang besar akan berada di luar negeri, padahal sebaliknya bilaIndonesia mampu mengekspor produk olahannya, maka dilai tambah terbesarnya akan berada di dalam negeri. Belajar dari kelemahan tersebut, sejak Pelita VI pembangunanpertanian dilakukan melalui pendekatan agribisnis, yang pada hakekatnya menekankan kepada tiga hal, yaitu:(1) pendekatanpembangunan pertanian ditingkatkan dari pendekatan produksi ke pendekatan bisnis, dengan demikian aspek usaha dan pendapatan menjadi dasar pertimbangan utama,(2) pembangunan pertanian bukan semata pembangunan sektoral, namun juga terkait dengan sektor lain (lintas/inter-sektoral),(3) pembangunan pertanian bukan pengembangan komoditas secara parsial, melainkan sangat terkait dengan pembangunan wilayah, khususnya perdesaan yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan pendapatan petani.Menyadari nilai tambah yang diperoleh dari pengembangan produk olahan (hilir) jauh lebih tinggi dari produk primer, maka pendekatan pembangunan pertanian ke depan diarahkan pada pengembangan produk, dan bukan lagi pengembangan komoditas dan lebih difokuskan pada pengembangan nilai tambah produk melalui pengembangan industri yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk plahan, baik produk antara (intermediate product), produk semi akhir (semi finished product) dan yang utama produk akhir (final product) yang berdayasaing. Untuk itu, salah satu strategi pembangunan pertanian ke depanadalah pengembangan agroindustri perdesaan.Pengembangan agroindustri perdesaan merupakan pilihan strategis dalam meningkatkan pendapatan dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Selama ini masyarakat perdesaan cenderung menjual produk dalam bentuk segar (primer), karena lokasi industri umumnya berada di daerah urban (semi-urban). Akibatnya, nilai tambah produk pertanian lebih banyak mengalir ke daerah urban, termasuk menjadi penyebab terjadinya urbanisasi.Tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan agroindustri perdesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui upaya peningkatan nilai tambah dan dayasaing hasil pertanian.Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pengembangan agroindustri perdesaan diarahkan untuk:a) mengembangkan kluster industri, yakni industri pengolahan yang terintegrasi dengan sentra-sentra produksi bahan baku serta sarana penunjangnya,b) mengembangkan industri pengolahan skala rumah tangga dan kecil yang didukung oleh industri pengolahan skala menengah dan besar, danc) mengembangkan industri pengolahan yang punya dayasaing tinggi untuk meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.Agenda utama pengembangan agroindustri perdesaan adalah penumbuhan agroindstri untuk membuka lapangan kerja di perdesaan, dengan kegiatan utama:a) Fasilitasi penerapan teknologi dan sarana pengolahan hasil pertanian di sentra-sentra produksi;b) Pengembangan infrastruktur penunjang di perdesaan seperti listrik, jalan akses, dan komunikasi;c) Pengembangan akses terhadap permodalan;d) Peningkatan mutu, efisiensi produksi dan pemasaran. Dalam rangka pengembangan produk hilir produk pertanian yang berdayasaing, inovasi teknologi yang berorientasi pasar dan berbasiskan sumberdaya domestik menjadi prasyarat keberhasilan pengembangan produk hilir pertanian ke depan.Dalam rangka mendorong terjadinya inovasi proses hilir produk pertanian yang bernilai tambah tinggi dan berdayasaing, dukungan berbagai kebijakan makro ekonomi sangat diperlukan. Disamping itu, pengembangan teknologi pengolahan dan produk pada produk hilir diarahkan untuk peningkatan efisiensi, pengembangan diversifikasi teknologi pengolahan untuk menghasilkan diversifikasi produk, dan meminimumkan kehilangan hasil.Dalam rangka pengembangan produk (porduct development) baru seperti pengembangan berbagai jenis industri oleo-pangan dan industri oleo-kimia akan didorong pengembangannya. Demikian pula pengembangan industri pengolahan karet lanjutan sepeti industri ban otomotif and barang jadi lain dari karet, pengembangan industri farmasi (tanaman obat-obatan), dan industri pengolahan berbasis hortikultura akan terus dikembangkan. Dalam rangka peningkatan dayasaing produk pertanian, disamping pengembangan produk hilir, ke depan pengembangan produk hulu juga didorong pertumbuhannya.Pengembangan industri perbibitan/perbenihan merupakan prasarat peningkatan dayasaing produk pertanian. Demikian juga pengembangan industri agrokimia dan alat serta mesin pertanian. Secara umum sasaran pembangunan pertanian jangka panjang (2025) adalah:a. terwujudnya pertanian industrial yang berdaya saing;b. mantapnya ketahanan pangan secara mandiri;c. tercapainya kesempatan kerja penuh bagi masyarakat pertanian;d. terhapusnya kemiskinan di sektor pertanian dan tercapainya pendapatan petani sebesarUS $ 2500/kapita/tahun.
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Strategi Umum dan KebijakanStrategi dan kebijakan pembangunan pertanian 2005-2009 disusun berlandaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Agenda pembangunan ekonomi dalam RPJMN yang terkait dengan pembangunan pertanian, antara lain:a. revitalisasi pertanian,b. peningkatan investasi dan ekspor non-migas;c. pemantapan stabilisasi ekonomi makro;d. penanggulangan kemiskinan;e. pembangunan perdesaan; danf. perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.Revitalisasi pertanian antara lain diarahkan untuk meningkatkan:a) kemampuan produksi beras dalam negeri sebesar 90-95 persen dari kebutuhan;b) diversifikasi produksi dan konsumsi pangan;c) ketersediaan pangan asal ternak;d) nilai tambah dan dayasaing produk pertanian;e) produksi dan ekspor komoditas pertanian. Strategi umum untuk mencapai Tujuan dan sasaran pembangunan pertanian adalah sebagai berikut:a. Melaksanakan manajemen pembangunan yang bersih, transparan dan bebas KKN.b. b.Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pembangunan pertanian.c. Memperluas dan memanfaatkan basis produksi secara berkelanjutan.d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memberdayakan SDM pertanian.e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.f. Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna.g. Mempromosikan dan memproteksi komoditas pertanian.Arah kebijakan yang perlu ditempuh dalam pembangunan pertanian jangka panjang adalah:a) Membangun basis bagi partisipasi petani;b) Meningkatkan potensi basis produksi dan skala usaha pertanian;c) c.Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sumberdaya insani pertanian yang berkualitas;d) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian:e) Mewujudkan sistem pembiayaan pertanian tepat guna;f) Mewujudkan sistem inovasi pertanian;g) Penyediaan sistem insentif dan perlindungan bagi petani;h) h.Mewujudkan system usahatani bernilai tinggi melalui intensifikasi, diverdifikasi dan pewilayahan pengembangan komoditas unggulan;i) Mewujudkan Agroindustri berbasis pertanian domestik di pedesaan;j) Mewujudkan system rantai pasok terpadu berbasis kelembagaan pertanian yang kokoh;k) Menerapkan praktek pertanian dan manufaktur yang baik; danl) Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berpihak kepada petani dan pertanian.Banyak kebijakan dan strategi yang terkait langsung dengan pembangunan pertanian, namun kewenangannya berada diberbagai instansi lain. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan makro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal,kebijakan pengembangan industri, kebijakan perdagangan, pemasaran, dan kerjasama internasional, kebijakan pengembangan infrastruktur khususnya pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan, kebijakan pengembangan kelembagaan (termasuk didalamnya lembaga keuangan, fungsi penelitian dan pengembangan, pengembangan SDM, dan pengembangan organisasi petani), kebijakan pendayagunaan dan rehabilitasi sumberdaya alam dan lingkungan, kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan baru, dan kebijakan pengembangan ketahananpangan.
Beberapa kebijakan strategis yang perlu ditekankan dan memerlukan penanganan segera yaitu:a) Kebijakan ekonomi makro yang kondusif yaitu inflasi yang rendah, nilai tukar yang stabil dam suku bungan riil positif.b) Pembangunan infrastruktur pertanian meliputi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, perluasan lahan pertanian terutama di luar Jawa, pencegahan konversi lahan terutama di Jawa, pengembangan jalan usahatani dan jalan produksi serta infrastruktur lainnya.c) Kebijakan pembiayaan untuk mengembangkan lembagakeuangan yang khusus melayani sektor pertanian, lembaga keuangan mikro, pembiayaan pola syaraiah, dan lainnya.d) Kebijakan perdagangan yang memfasilitasi kelancaran pemasaran baik di pasar dalam negeri maupun ekspor. Selain itu, untuk melindungi sektor pertanian dari persaingan di pasar dunia, diperlukan: (a) memperjuangkan konsep Strategic Product (SP) dalam forum WTO; (b) penerapan tarif dan hambatan non-tarif untuk komoditas-komoditas beras, kedelai, jagung, gula, beberapa produk hortikultura dan peternakan.e) Kebijakan pengembangan industri yang lebih menekankan pada agroindustri skala kecil di perdesaan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petanai.f) Kebijakan investasi yang kondusif untuk lebih mendorong minat investor dalam sektor pertanian.g) Pembiayaan pembangunan yang lebih memprioritaskan anggaran untuk sector pertanian dan sektor-sektorpendukungnya.h) Perhatian pemerintah daerah pada pembangunan pertanian meliputi: infrastuktur pertanian, pemberdayaan penyuluh pertanian, pengembangan instansi lingkup pertanian, menghilangkan berbagai pungutan yang mengurangi dayasaing pertanian, serta alokasi APBD yang memadai.
Beberapa kebijakan yang langsung terkait dengan sektor pertanian dan dalam kewenangan atau memerlukan masukan dari Departemen Pertanian adalah:a. Kebijakan dalam pelaksanaan manajemen pembangunan yang bersih, transparan, dan bebas KKN, diarahkan untuk menyusun kebijakan peningkatan kesejahteraan pegawai disertai penerapan reward and punishment secara konsisten.b. Kebijakan dalam peningkatan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pembangunan pertanian, diarahkan untuk: (a) peningkatan keterbukaan dalam perumusan kebijakan dan manajemen pembangunan pertanian, (b) peningkatan evaluasi, pengawasan, dan pengendalian manajemen pembangunan pertanian, (c)penyelarasan pembangunan pertanian antar sektor dan wilayah.c. Kebijakan dalam memperluas dan meningatkatkan basis produksi secara berkelanjutan diarahkan untuk: (a) peningkatan investasi swasta, (b) penataan hak, kepemilikan dan penggunaan lahan, (c) kebijakan pewilayahan komoditas, dan (d) penataan sistem pewarisan lahan pertanian.d. Kebijakan dalam meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan SDM pertanian diarahkan untuk: (a) menyusun kebijakan revitalisasi penyuluhan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan pertanian, (b) peningkatan peran serta masyarakat, (c) peningkatan kompetensi dan moral aparatur pertanian, (d) penyelenggaraan pendidikan pertanian bagi petani, dan (e) pengembangan kelembagaan petani.e. Kebijakan dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian diarahkan untuk: (a) pengembangan sarana dan prasarana usaha pertanian, (b) pengembangan lembaga keuangan perdesaan, (c) pengembangan sarana pengolahan dan pemasaran.f. Kebijakan dalam meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna diarahkan untuk: (a) merespon permasalahan dan kebutuhan pengguna, (b) mendukung optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pertanian spesifik lokasi, (c) pengembangan produk berdayasaing, (d) penyelarasan dan integrasi dengan penguasaan IPTEK pertanian, dan (e) percepatan proses dan perluasan jaringan diseminasi dan penjaringan umpan balik inovasi pertanian.g. Kebijakan dalam meningkatkan promosi dan proteksi komoditas pertanian, diarahkan untuk: (a) menyusun kebijakan subsidi tepat sasaran dalam sarana produksi, harga output, dan bunga kredit untuk modal usahatani (b) peningkatan ekspor dan pengendalian impor, (c) kebijakan penetapan tarif impor dan pengaturan impor, (d) peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha, (e) perbaikan kualitas dan standardisasi produk melalui penerapan teknologi produksi, pengelolaan pascapanen dan pengolahan hasil, dan (f) penguatan sistem pemasaran danperlindungan usaha.18-06-2013
Perkembangan KTT APEC Bali 2013
Indonesia Harus Perjuangkan Kedaulatan Pangan dan Kebijakan Pertanian Pro Rakyat di KTT APEC Bali 2013
Penulis : Ferdiansyah Ali dan Hendrajit, Peneliti Global Future Institute
The world is looking to APEC as the engine for global growth because the Asia Pacific region has demonstrated its resilience in the wake of the most recent financial crisis President Susilo Bambang Yudhoyono at the APEC CEO Summit 2012 Vladivostok.
Kalau kita mencermati beberapa agenda strategis yang dipersiapkan para pemangku kebijakan ekonomi dan politik luar negeri Indonesia menyongsong keketuaan dan ketuanrumahan Indonesia pada pada KTT APEC Oktober 2013 mendatang, sebenarnya cukup menjanjikan.Setidaknya dalam forum pertemuan para pejabat senior APEC 2013 di Surabaya 7-19 April lalu, telah mencanangkan beberapa isu prioritas yang mencakup antara lain:1. Pembangunan dan investasi infrastruktur2. Program pemberdayaan perempuan dalam perekonomian3. Peningkatan daya saing UKM (Usaha Kecil dan Menengah)4. Perluasan akses kesehatan5. Promosi kerja sama pendidikan lintas negara6. Rencana kerangka konektivitas di Asia Pasifik yang akan memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat Asia Pasifik untuk berpergian dan melangsungkan perdagangan.
Dari enam agenda yang secara eksplisit telah disampaikan oleh Yuri O Thamrin, Ketua Sidang Pejabat Senior APEC 2013 yang juga menjabat Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri, kiranya sudah cukup jelas secara konseptual.
Namun dari penilaian Global Future Institute, terkesan agenda-agenda strategis tersebut tidak ditempatkan dalam kerangka strategi kebijakan luar negeri dan sudut pandang geopolitik untuk memberdayakan posisi tawar Indonesia dalam menghadapi kepentingan-kepentingan strategis korporasi-korporasi global asing, terutama Amerika dan Uni Eropa.Sehingga dikhawatirkan Indonesia justru akan masuk dalam perangkap skema dan strategi kebijakan kapitalisme global di Washington dan Uni Eropa yang tergabung dalam G-7.
Maka sebagai latarbelakang dan pemetaan masalah sebelum kita sampai pada perumusan agenda-agenda strategisnya, ada baiknya para pemangku kepentingan yang terlibat dalam perumusan kebijakan strategis pada KTT APEC mendatang untuk mendalami terlebih dahulu kondisi obyektif yang berkembag di tanah air saat ini.
Mari kita simak kondisi obyektif di sektor pertanian, sekadar sebagai contoh.
Rapuhnya Kedaulatan Sektor Pertanian dan Pangan Indonesia
Pertama, saat ini Indonesia yang merupakan negara agraris dan menjadi lumbung hortikultura (sayur, buah-buahan dan bunga), namun anehnya malah mengalami kelangkaan. Masalah kelangkaan dan tingginya harga produk-produk hortikultura sesungguhnya tidak perlu terjadi di Indonesia.
Sebagai negara yang memiliki dua musim sebenarnya potensi Indonesia sebagai penghasil produk-produk unggulan hortikultura hampir saja tidak memiliki pesaing. Artinya bahwa potensi Indonesia sungguh besar, yatu memiliki kekayaan sumberdaya komoditas pertanian yang tinggi serta ketersediaan lahan pertanian yang lebih luas. Variasi topografi dan model demografi untuk menghasilkan produk yang bervariasi juga terbuka luas.
Kedua, dengan merujuk pada pendapat Sabiq Carebesth, Pemerhati masalah Ekonomi Politik Pangan Jurnal Sosial Agraria Agricola, dalam sebuah sistem, kegiatan kerja bertani tidak lagi semata-mata dilihat sebagai sebuah kebudayaan bercocok tanam, melainkan bisnis. Bisnis lalu menyangkut politik berupa lobi-lobi, patgulipat, kongkalikong, aturan pun diselenggarakan; siapa yang berhak memproduksi, mengedarkan, dan siapa yang masuk dalam perencanaan sebagai sasaran pengguna sekaligus disebut korban. Pengedarnya adalah pebisnis, yaitu mereka yang punya naluri, tenaga dan modal untuk menjadikan benih sebagai sumber keuntungan.
Keuntungan itu lalu diakumulasi. Akumulasi keuntungan itu lalu terkonsentrasi hanya di tangan segelintir para pebisnis yang menciptakan sistem monopoli. Monopoli lalu menjadikan sistem perbenihan dan pertanian khususnya membangun oligopoli, Lantas siapa target sasaran bisnisnya yang kemudian jadi korban? Yang jadi korban adalah para Petani kecil yang pada dasarnya masuk golongan ekonomi lemah dan kecil.
Merekalah target dari eksploitasi sistematis pemiskinan yang akan berlangsung pelan-pelan melalui politik ketergantungan. Mula-mula benih, lama-lama pestisidanya, lalu yang paling parah adalah sistem bercocok tanamnya, lalu corak bermasyarakatnya.
Maka, monopoli tak terhindarkan, kartel menerapkan paham stelsel. Kartel domestik pada industri benih di dalam negeri telah diduga dilakukanWorld Economic Forum Partnership on Indonesian Sustainable Agriculture(WEFPISA) yang beranggotakan perusahaan-perusahaan multinasional yang telah lama mengincar pasar benih dan pangan di Indonesia.
Kartel PanganSementara itu, masih menurut Sabiq Carebesth, kartel internasional dan nasional pada sektor pangan diduga mengendalikan harga, stok, dan pasokan komoditas pangan utama di dalam negeri. Di pasar internasional, setidaknya terdapat 12 perusahaan multinasional yang diduga terlibat kartel serealia, agrokimia, dan bibit tanaman pangan. Di dalam negeri ada 11 perusahaan dan enam pengusaha yang ditengarai menjalankan kartel kedelai, pakan unggas, dan gula.Negara sebagai sebuah institusi pelindung rakyat akhirnya harus berhadap-hadapan dengan organisasi perdagangan yang memang berorientasi mengakumulasi keuntungan. Tak pelak keanggotaan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah membuka jalan bagi perusahaan multinasional memonopoli usaha perbenihan dan pangan.Komite Ekonomi Nasional (KEN) misalnya menyebutkan di pasar internasional terdapat empat pedagang besar yang disebut ABCD, yaitu Acher Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, dan Louis Dreyfus. Mereka menguasai sekitar 90 persen pangsa perdagangan serealia (biji-bijian) dunia. Struktur pasar komoditas pangan juga memiliki kecenderungan oligopolistik.Dalam industri agrokimia global juga terdapat enam perusahaan multinasional, yaitu Dupont, Monsanto, Syngenta, Dow, Bayer, dan BASF yang menguasai 75 persen pangsa pasar global. Dalam industri bibit terdapat empat perusahaan multinasional, yakni Monsanto, Dupont, Syngenta, dan Limagrain, dengan penguasaan 50 persen perdagangan bibit global.Pada sektor pangan, kartel juga terjadi pada industri pangan dan impor. Indikasinya, satu per satu perusahaan makanan domestik diakuisisi perusahaan asing. Misalnya, Aqua diakuisisi Danone (Prancis), ABC diakuisisi Unilever (Inggris), dan Kecap Bango dikuasai Heinz (Amerika). Sementara itu, tren misalnya pada impor daging mayoritas rupanya dari Australia, bawang putih dari Tiongkok, dan bawang merah dari Filipina.Belum lagi apa yang disampaikan oleh pengamat ekonomi pertanian UGM, Prof. Dr. Moch. Maksum Machfoedz, dimana sembilan komoditas pangan nasional hampir semuanya impor. Disebutkan bahwa komoditas gandum dan terigu masih impor 100%, bawang putih 90%, susu 70%, daging sapi 36%, bibit ayam ras 100%, kedelai 65%, gula 40%, jagung 10%, dan garam 70%.Sementara informasi yang disampaian Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan, mengatakan produksi dan distribusi sayuran seperti tomat, cabai, seledri dan bawang di kawasan Garut dan Lembang juga telah dikuasai oleh Indofood Frito Lay, Heinz ABC, dan Del Monte. Sedangkan produksi dan distribusi kacang-kacangan, jagung, dan serelia di kawasan Bandung Timur, Subang, dan Purwakarta dikuasai oleh Cargill dan Charoen Pokphand.Bidang saprotan, juga tidak lepas dari dominasi perusahaan asing dengan beroperasinya Ciba Geigy dari Jepang, BASF dan Bayer dari Jerman, serta Novartis dari Amerika Serikat yang menguasai jalur distribusi pestisida.Hal serupa juga terjadi di bidang pembenihan dengan kehadiran Monsanto yang mengembangkan bibit jagung dan kedelai, serta beberapa perusahaan Jepang untuk bibit sayuran.Hal tersebut kemudian berdampak langsung pada maraknya kriminalisasi dan hilangnya kedaulatan petani dalam mengelola sumber pangan nasional, target swasembada pangan berkala pada 2014 akan jadi isapan jempol belaka. Tak pelak, Indonesia terperangkap dalam liberalisasi perdagangan yang mengakibatkan Indonesia dibanjiri produk pangan dan manufaktur impor.
Amerika Serikat Tekan Indonesia Agar Cabut Pembatasan Impor Holtikultura
Masih soal holtikultura, satu lagi kenyataan obyektif yang kiranya Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perekonomian perlu mencermati secara seksama. Beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia akhirnya mengalah menyikapi laporan Pemerintah Amerika Serikat ke Badan Perdagangan Dunia (WTO), atas peraturan impor hortikultura dengan melakukan pelarangan dan pembatasan buah dan sayuran. Karenanya, Pemerintah akan melakukan revisi Permentan nomor 60 Tahun 2012 tentang rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH).
Hal ini terkait dengan langkah Indonesia memberlakukan Permentan No. 60 tahun 20012 tentang pembatasan impor Holtikultura (sayur dan buah), sehingga AS) gencar memprotes aturan tersebut. Bahkan Indonesia diadukan ke WTO. Setelah melakukan pertemuan antara perwakilan AS dan Indonesia di Jenewa beberapa waktu lalu akhirnya pemerintah indonesia berencana merevisi aturan tersebut.
Pemerintah mengeluarkan aturan Permentan 60 Tahun 2012 dan Permendang Nomor 60 Tahun 2012 terkait pengaturan importasi 20 komoditas hortikultura.
Aturan tersebut dikeluarkan karena dianggap produksi dalam negeri masih mencukupi sehingga pemerintah melarang 13 komoditas hortikultura masuk ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu, diantaranya durian, nanas, melon, pisag, mangga, pepaya, kentang, kubis, wortel, cabe, krisan, anggrek dan heliconia.
Sementara 7 komoditas hotrikultura yang dibatasi jumlah impornya di antaranya Bawang yang diterdiri dari bawang bombay, bawang merah dan bawang putih, kemudian Jeruk yang terdiri dari jeruk siam, jeruk mandarin, lemon, dan grapefruit atau pamelo, anggur, apel dan lengkeng.
Dari 300 Komoditas hanya 90 sampai 92 komoditas yang diperdagangkan. Dari jumlah itu 20 komoditas yang diatur dalam Permentan nomor 60 Tahun 2012. Dari 20 komoditas tersebut 7 komoditas hortikultura yang dibatasi jumlah kuota impornya.
Dari gambaran tersebut di atas, pemerintah Indonesia sudah seharusnya menyadari adanya sisi rawan dari kedaulatan kita di sektor pertanian dan sektor pangan, akibat kuatnya pengaruh dan tekanan korporasi-korporasi asing dalam pembuatan kebijakan strategis di sektor pertanian dan pangan.
Dan yang yang mengecewakan kami dari Global Future Institute, pemberdayaan sektor pertanian dan pangan sama sekali tidak dimasukkan sebagai salah satu isu prioritas sebagaimana disampaikan oleh Yuli O Thamrin pada Sidang Pertemuan Pejabat Senior APEC di Surabaya April lalu.
Padahal, berdasarkan data kementerian Pertanian menunjukan perkembangan impor buah dan sayur mengalami perkembangan yang sangat drastis. Pada tahun 2008, nilai impor produk hortikultura mencapai 881,6 juta dollar AS, tetapi pada 2011 nilai impor produk hortikultura sudah mencapai 1.7 miliar dollar AS (dengan kurs Rp. 9.500, sekitar Rp 16,15 triliun).
Komoditas hortikultura yang di impornya paling tinggi adalah bawang putih senilai 242,4 juta dollar AS (sekitar Rp. 2,3 triliun), buah apel sebanyak 153,8 juta dollar AS (sekitar Rp. 1,46 triliun), jeruk 150,3 juta dollar AS (sekitar Rp. 1,43 triliun) serta anggur sebanyak 99,8 juta dollar AS (sekitar Rp. 943 miliar).
Karena itu kita kiranya cukup beralasan dengan membanjirnya produk holtikultura impor. Seakan produk holtikultura tidak mampu bersaing, padahal kita sangat mampu bersaing di tingkat internasional.
Padahal pada kenyataannya, Komoditas hortikultura lokal selama ini telah memberikan pendapatan yang besar bagi negara, Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) hortikultura terus meningkat dari tahun ke tahun. Angka PDB hortikultura tahun 2005 sebesar Rp 61.729 miliar meningkat menjadi Rp 88.334 miliar pada tahun 2010. Dengan PDB terbesar di sumbang dari komoditas buah, disusul sayuran, hias dan tanaman obat.Mengapa hal ini bisa terjadi? Maka penyebabnya adalah besarnya pengaruh skema kapitalisme global lewat beberapa korporasi asing, sehingga holtikultra produk import bisa merajalela di Indonesia.
Pada tataran ini, Indonesia dalam KTT APEC 2013 harus punya kontra skema untuk mematahkan monopoli kartel-kartel asing tersebut. Sehingga agenda-agenda strategis Indonesia pada KTT APEC 2013 mendatang benar-benar membumi.
Kontra Skema Indonesia dalam KTT APEC 2013 harus didasari gagasan untuk melakukan proteksi terhadap kelompok-kelompok ekonomi menengah dan kecil. Pada tingkatan ini, merumuskan perlunya peningkatan daya saing UKM dimasukkan dalam salah satu isu prioritas kiranya sudah berada di jalan yang tepat. Hanya saja belum tergambar secara jelas strategi pemerintah Indonesia dalam menjabarkan isu tersebut pada KTT APEC 2013 mendatang.
Dalam hal kedaulatan atau kemandirian pangan, misalnya, harus didasari untuk melindungi kepentingan para petani. Program kemandirian pangan berarti juga harus diikuti dengan diberlakukannya kebijakan melarang pemberlakuan bebas bea masuk pangan impor. Sehingga skema kedaulatan ekonomi dan khususnya pangan, akan mampu membendung gempuran produk-produk impor dari luar negeri terhadap produk dalam negeri.
Dalam hal memberlakukan kebijakan proteksi terhadap pertanian dalam negeri, ada baiknya mencontoh Cina dan Rusia. Bagaimana kedua negara tersebut ketika memberlakukan kebijakan pertanian pro rakyat dalam bidang unggas misalnya, pakan pun diproteksi, bahkan diberikan secara gratis, untuk melindungi para petaninya.
Dengan mengambil inspirasi dari Cina maupun dari Rusia, yang kebetulan saat ini menjadi menjadi Ketua APEC menyusul KTT APEC di Vladivostok tahun lalu, sudah saatnya pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pangan yang pro pertanian. Dengan memberikan perlindungan terhadap petani mulai dari harga jual, bibit, pakan, bahkan hingga kebijakan agro industry yang melindungi petani.
Apalagi diperkuat oleh berbagai fakta yang disampaikan beberapa pakar bahwa pangan lokal ternyata memiliki potensi lebih baik daripada bahan impor karena kesesuaian biologis yang lebih tinggi dengan manusia dan mikrobiota lokal Indonesia.
Saatnya pemerintah harus tegas dan konsisten dengan target pencapaian kedaulatan pangan. Jangan mau diatur-atur oleh para importir. Dalam fluktuasi harga pangan, sudah beberapa kali pemerintah dipermainkan oleh kelompok tertentu karena Indonesia tidak mandiri dalam hal pangan. Pola yang sama digunakan para importir saat terjadi kelangkaan kedelai beberapa waktu lalu.
SOLUSI PEMBANGUNAN PERTANIAN INDONESIA UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN PANGANOleh: Karta Jaya H TambunanPertanian merupakan jantung pertahanan bagi ketahanan pangan Indonesia saat ini. Selain itu juga, pertanian adalah sektor utama penyedia bahan pangan, baik bagi manusiamaupun pakan bagi ternak/hewan dan ikan yang merupakan bagian dari siklus pertanian itu sendiri. Meninggalkan sektor pertanian dalam pembangunan nasional, terutama dalam ketahanan panganakan membawa bangsa ini kepada krisis. Namun, membangun pertanian Indonesia tanpa komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan akan membawa bangsa ini kepada krisis keadilan juga. Dari gambaran krisis ini, terdapat kaitan yang sangat erat antara ketahanan pangan dan pertanian yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa pertanian yang maju, ketahanan pangan tidak akan sukses, dan tanpa ketahanan pangan yang baik, bangsa ini akan mengalami suatu masalah yang sangat serius yaitu kelaparan dan kemiskinan. Tetapi masalah itu dapat kita selesaikan dengan menjadikan pertanian Indonesia yang menjadi solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan di negara kita.Mendorong pembangunan pertanian yang menjanjikan merupakan salah satu usaha untuk mensejahterakan rakyatIndonesia khususnya. Tentu pemikiran ini adalah sebuah langkah untuk menaggapi permasalahan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Usaha memajukan pertanian ini akan terus disempurnakan sehingga sampai pada langkah-langkah operasional yang diperlukan pemangku kepentingandalam pemberdayaan pertanian ini.Berbagai bentuk krisis pangantelah terjadi selama ini yang merupakan bukti bahwa lemahnyasektor pertanian dalam pemenuhan pangan di Indonesia, sehingga mengakibatkan banyak terdapat keluarga petani Indonesia yang ketahanan pangannya rendah yang mengakibatkan kemiskinan bahkan menimbulkan penyakit kekurangan gizi pada anak-anak dan penyakit busung lapar. Sehingga solusi terhadap persoalan pangan iniakan selalu terkait denganmasalah kemiskinan dan kelaparan.Kesejahteraanpetaniyang relatif rendahsaat iniakan sangat menentukan prospek ketahanan pangandi Indonesia ke depannya. Kesejahteraan tersebut diakibatkan oleh berbagai faktor yang timbul dan keterbatasan petani, diantaranya yangpalingutama adalah :a.Sebagian petani miskin karena memang tidak memiliki faktor produktif yang mendukung pekerjaan mereka,kecuali tenaga kerjanyab. Luas lahan pertanian yang sempit dan mendapat tekanan untuk terus terkonversic.Terbatasnya akses terhadap dukungan layanan pembiayaandan penyuluhan pertaniand.Tidak adanya atau terbatasnya akses terhadap informasi dan teknologi yang lebih memadai untuk mereka terapkane. Infrastruktur produksi (air, listrik, jalan, telekomunikasi) yang tidak memadaif. Struktur pasar yang tidak adil dan eksploitatif akibat posisi rebut-tawar yang sangat lemahg. Ketidak-mampuan, kelemahan, atau ketidak-tahuan petaniitusendiri.Estimasi kebutuhan pangan yang ideal harus disediakan dan dikonsumsi masyarakat untuk mencapai gizi seimbang yang dapat diproyeksikan dengan pendekatan interpolasi linier untuk mencapai Skor PPH 100 pada tahun 2020. Penetepan angka 2020 ini merupakan kesepakatan yang diambil dan didasarkan atas pertimbangan bahwa setelah mencapai MDGs (Millenium Development Goals) tahun 2015 (menurunkan kelaparan sampai setengahnya). Adapun Proyeksi Konsumsi dan Penyediaan Pangan di Indonesia dengan mengacu PPH pada tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini.NoKelompok/Jenis PanganKonsumsiPenyediaan
1Padi-padian--
Beras21.72823.901
Jagung307337
Terigu1.9612.158
Subtotal Padi-padian23.98726.386
2Umbi-umbian--
Ubi Kayu5.2425.767
Ubi Jalar1.2331.357
Sagu222245
Kentang768845
Umbi Lainnya384423
Subtotal Umbi-umbian7.8508.635
3Pangan Hewani--
Ikan7.5128.263
Daging Ruminansia671738
Daging Unggas1.1031.214
Telur2.2912.520
Susu658724
Subtotal Pangan Hewani12.21213.433
4Sayur dan Buah--
Sayur14.27715.705
Buah5.7856.363
Subtotal Sayur dan Buah20.06222.068
5Minyak dan Lemak
Minyak Kelapa906996
Minyak Sawit1.2331.356
Minyak Lain4247
Subtotal Minyak dan Lemak2.1812.399
6Kacang-kacangan
Kacang Tanah223245
Kacang Kedelai2.5332.786
Kacang Hijau227-
Kacang lain--
Subtotal Kacang-kacangan3.0533.358
7Gula--
Gula Pasir2.2482.472
Gula Merah269296
Sirup--
Subtotal Gula2.6172.878
8Sayur dan Buah--
Sayur14.27715.705
Buah5.7856.363
Subtotal Sayur dan Buah20.06222.068
9Lain-Lain--
Minuman885974
Bumbu419461
Lainnya--
Subtotal Lain-Lain1.3081.439
Sumber : Martianto dkk (2006)Pada tabel di atas terlihat, bahwa sepanjang terdapat konvergensi dari jaminan interpolasi linear ini maka ketahanan pangan nasional tidak akan berkurang. Namun, masalahnya sekarang adalah masih adanya kekurangan dalam tatanan distribusi, akses, dan konsumsi dari bahan pangan tersebut. Pada kenyataannya hal ini sangat sulit untuk diatasi, sehingga menyebabkan kenaikan harga pangan di pasar sangat pesat dibanding tahun 2007 yang mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal juga.Adapun faktor eksternal adalah : 1) adanya kenaikan harga pangan di pasar dunia, 2) menurunnya produksipangan dunia karena perubahan iklim terutama masalah kekeringan di negara produsen serta menurunnya luas areal panen, 3) pengaruh kenaikan harga minyak bumi yang menyebabkan ongkos produksi naik, 4) adanya perubahan iklim global dan konversi komoditas pangan ke bahan bakar nabati, 5) adanya penguasaan perdagangan biji-bijian oleh beberapa korporasi multinasional, dan 6) masuknya investor di bursa komoditas. Penyebab faktor internalnya adalah: 1) adanya konversi lahan sawah untuk pemukiman dan industri, 2)luas areal panen hanya mengalami peningkatan yang sangat kecil (sekitar 1,4 % pada tahun 2008), 3) produktivitas relatif tetap, 4) margin yang diterima petani untuk tanaman pangan sangat rendah dibandingkan komoditas hortikultura, dan 5) harga komoditas tanaman pangan yang relatif rendah.Pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin pesat juga dapat mempengaruhi ketahanan pangan suatu negara. Penduduk Indonesia pada tahun 2035 diperkirakan akan bertambah menjadi 2 kali lipat dan jumlahnya sekarang, menjadi 400 juta jiwa. Dengan meningkatnya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, terjadi pula peningkatan konsumsi/kapita untuk berbagai pangan. Akibatnya, dalam waktu 35 tahun yang akan datang Indonesia memerlukan tambahan ketersediaan pangan yang lebih dari 2 kali jumlah kebutuhan saat ini.Penduduk Indonesia 1900 - 2035TahunJumlah
190019301960199020002035 40 juta 60 juta 95 juta 180 juta 210 juta 400 juta
Diawal abad ke 20, selama 30 tahun penduduk Indonesia bertambah 20 juta jiwa, dan diawal abad 21, selama 30 tahun penduduk Indonesia bertambah hampir 200 juta jiwa. Penduduk Indonesia menjadi 5 kali lipat dalam waktu 100 tahun.Akibat pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan produksi bahan pangan yang menurun di Indonesia, mengakibatkan Indonesia harus mengimpor bahan pangan dari luar negeri. Contoh konkritnya adalah kedelai yang diimpor pada tahun 1990-1998 hanya berkisar antara 343.000-541.000 ton, meningkat tajam sejak tahun 1999-20007 menjadi antara 1.133.000-1.343.000 ton.Dari permasalahan di atas, dapat kita berikan argumen bahwa pertanian Indonesia masih memerlukan perhatian yang sangat serius dari berbagai pihak untuk mensejahterakan petani dan untuk meningkatkan ketahanan pangan di negara ini. Dan tidak lepas dari perhatian pemerintah sebagai penyelenggara peraturan, pembinan dan pengawas terhadap pertanian Indonesia. Masalah-masalah yang dihadapi negara kita inibukanlah yang pertama kali terjadi di dunia ini. Masalah yang kita alami initelah pernah dialami oleh banyak negara lain dan banyak yang dapat mengatasinya dengan sukses.Seharusnya negara kita belajar dari pengalaman negara tersebut untuk mengatasi masalah yang ini. Di samping itu juga peran masyarakat maupun pihak swasta juga sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini serta memajukan pertanian Inndonesia yang berkelanjutan.Agar penbangunan pertanian memiliki arah yang jelasdan berkesinambungan, negara perlu menetapkan politik pertanianyaitu keputusan sangat mendasar dibidang pertanian pada tingkat negara, yang menjadi arah ke depan, untuk menjadi acuan semua pihak yang terlibat, dengan sasaran membangun kemandirian di bidang pangan.Memang, isu tentang penbangunan pertanian sudah cukup lama dibahas, namun hingga saat ini belum terlihat langkah-langkah yang kongkret serta efektifuntuk meningkatkan pertanian yang mandiri. Yang terjadi malah Indonesia semakin tergantung dengan impor bahan pangan,serta kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah justru semakin menekan pertanian Indonesia itu sendiri, seperti membebaskan bea masuk untuk impor gandum dan kedelaiyang menguasai pasar Indonesia.Padahal pertanian Indonesia sangat mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. Untuk itu pemerintah berperan dalam memfasilitasi kondisi yang kondusif bagi masyarakat dan swasta untuk berkiprah dalam pembangunan pangandalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Selain pemerintah, kita juga perlu menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk menanggulangi masalah ketahanan pangan ini. Dan inimenjadi tanggung jawab semua pihak. Untuk itu perlu dikembangkan suatu komitmen dan kerjasama diantara semua pihak terutama dalam bentuk kerjasama yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat (yang antara lain direpresentasikan oleh kalangan LSM dan perguruan tinggi).Tugas pemerintah adalah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan terhadap ketersediaan pangan, kecukupan , perataan pangan, baik dalam jumlah, mutu, aman, bergizi, beragam, serta harga, distribusi, daya beli masyarakat. Upaya untuk terciptaanyakondisi tersebut, makapemerintahmenetapkan target pembangunan pertanian Indonesia ke depannya, yaitu peningkatan pada produksi dan swasembada yang berkelanjutan, diversifikasi pangan,nilai tambahpada produk pertanian Indonesia, daya saingdengan produk luar, ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan dengan visi pertanian Indonesia tahun 2009-2014 adalah menjadikan Pertanian Indonesia menjadi pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, perspektif baru yang harus diterapkan adalah perspektif pembangunanpertanianyangberkedaulatan berkeadilan, , danberkelanjutanyang harus mewarnai pembangunan dan penataan sektor dan bidang-bidang tersebut. Ketiga prinsip tersebut didasarkan pada akar persoalan bangsa Indonesia yang masih terperangkap ke dalam ketergantungan dengan pihak asing baik dalam pemikiran pembangunan, peraturan perundangan, formulasi dan implementasi kebijakan, aspek-aspek kehidupan sosial, maupun birokrasi.Prinsip-prinsip pembangunan yang berkedaulatan adalah mencakup hal-hal di bawah ini :1) Pemikiran pembangunan yang lebih mencerminkan kepada kedaulatan rakyat2) Peraturan perundang-undangan yang mencerminkan kedaulatan dan pemihakan terhadap kepentingan rakyat banyak3) Kebijakan ekonomi-politik yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat4) Berdaulat dalam pengalokasian sumber-sumber keuangan untuk kesejahteraan rakyat5) Rezim devisa yang lebih berdaya guna untuk pengembangan ekonomi yang mensejahterakan rakyat6) Kedaulatan atas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat7) Perlindungan dan penguatan terhadap munculnya kelompok-kelompok tani, nelayan, peternak, perkebunan yang berdaulat dalam mengatur dan mengembangkan sumberdaya.Prinsip-prinsip pembangunan yang berkeadilan adalah sebagai berikut :1) Pemikiran pembangunan yang lebih menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat2) Kesetaraan akses, pemanfaatan, dan kontrol bagi rakyat atas sumber-sumber ekonomi3) Kebijakan ekonomi-politik yang lebih berkeadilan bagi rakyat banyak4) Keadilan dalam alokasi sumber-sumber keuangan untuk mengoreksi ketimpangan sosial ekonomi5) Penegakan hukum untuk menjamin keadilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber sumber ekonomi bagi rakyat banyakAdapun prinsip-prinsip berkelanjutan adalah sebagai berikut :1) Integrasi prinsip-prinsip yang berkelanjutan dalam formulasi kebijakan, rencana, dan program pembangunan2) Pemulihan kualitas lingkungan dan stok sumberdaya alam untuk mencegah ancaman terhadap ketidakberlanjutan pembangunanPerspektif baru pembangunan pertanian ini mengajukan sumberdaya alam domestik untuk dikelola dengan berbasis IPTEK yang tepat guna, memadai, dan mempunyai daya dukung lingkungan. Sehingga perspektif pembangunan pertanian ini membutuhkan peran negara dan pasar secara proporsional, tepat guna, dan bijak. Dalam kaitan tersebut, terdapat peluang untuk menciptakan kebijakan fiskal progresif yang membangun infrastruktur pertanian dalam arti luas dan perdesaan yang ditopang oleh kebijakan moneter yang tepat serta pergeseran dari kebijakan sistem perbankan berbasis cabang kepada sistem perbankan yang berbasis unit dimana pengembangan kebutuhan kredit diidentifikasikan berdasarkan stimulus lokal. Dengan perspektif baru tersebut maka diperlukan pengarahan kembali (redirecting) strategi dan kebijakan pembangunan yang diharapkan mencapai bangsa mandiri yang didukung pertanian dan pedesaan yang tangguh untuk meningkatkan ketahanan pangan. Berdasarkan analisis terhadap krisis-krisis bangsa khususnya pangan, maka reorientasi kebijakan dasar yang diperlukan adalah perubahan strategi pembangunan dan penataan ruang berimbang yang berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan, reforma agraria, percepatan pembangunan pedesaan. Pengarahan kembali strategi dan kebijakan ini dilakukan berdasarkan isu-isu krisis bangsa yang sekarang ini terjadi. Perspektif baru pembangunan merupakan kerangka memandang strategi dan kebijakan di bidang ekonomi, pangan, ekologi, dan pertanian.
MANAJEMEN AGRIBISNIS DAN KEWIRAUSAHAANOleh: Ir. Gunarif Taib, M.Si.I. PERANAN SEKTOR PERTANIANPenduduk Sumatera Barat berjumlah 4,6 juta jiwa atau 1,1 juta KK (Kepala Keluarga) dan 60 persen diantaranya (640.000 KK) bergerak dalam sektor pertanian. Kalau dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat Tahun 2006 maka sektor petanian hanya memberikan kontribusiya 25,26 persen yang terdiri dari tanaman pangan 13,11%, perkebunan 5,60%, peternakan 2,04%, kehutanan 1,50%, dan perikanan 3,01%. Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian ini diperlukan terobosan antara lain berupa upaya peningkatan efisiensi biaya produksi dan mengusahakan adanya nilai tambah melalui proses penanganan dan pengolahan hasil produk pertanian. Peningkatan efisiensi biaya produksi bisa dicapai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien, untuk itu aspek manajerial dalam usaha tani perlu mendapat perhatian selain dari upaya penerapan teknologi. Proses nilai tambah bisa diperoleh melalui penanganan pada pasca panen seperti melakukan sortasi/grading dan pengemasan sehingga harga jual bisa ditingkatkan. Selain itu juga bisa dilakukan pengolahan bahan segar menjadi produk olahan yang mempunyai prospek pasar cukup baik. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam berwirausaha pada sektor pertanian khususnya dalam penanganan dan pengolahan hasil tersebut perlu diperhatikan aspek manajemen dalam pemanfaatan sumberdaya yang ada. Saat ini wirausaha di sektor pertanian umumnya dikuasai oleh pedagang sehingga petani hanya diposisikan sebagai penerima harga sedangkan penentuan harga berada di tangan pedagang. Hal ini sangat merugikan petani karena keuntungan terbesar sesungguhnya berada pada tata niaga/pemasaran dan industri pengolahan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan pemberdayaan petani untuk bisa bergerak pada rantai tata niaga dan industri pengolahan. Upaya ini akan sulit dilakukan bila petani bergerak secara perorangan sehingga diperlukan pembentukan kelompok yang solid. Dalam kegiatan kelompok perlu diperhatikan aspek manajemen sehingga kelompok tersebut mempunyai perencanaan yang baik, mampu melakukan evaluasi dengan tepat dan semua kegiatan terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian diharapkan kelompok bisa berkembang dengan cepat dan keuntungan secara ekonomis bisa diperoleh. Dalam pengelolaan kegiatan agribisnis juga perlu diperhatikan karakteristik komoditi pertanian yang sangat spesifik untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian dalam berusaha.II. KARAKTERISTIK PRODUK PERTANIAN Manajemen Agribisnis merupakan bagian dari ilmu manajemen yang spesifik karena berhadapan dengan produk pertanian yang mempunyai sifat khusus sebagai berikut :1. Mudah rusak Produk pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura sangat mudah rusak sehingga harus segera dipasarkan atau diolah menjadi produk olahan. Dalam hal ini bila produk akan dipasarkan dalam bentuk segar maka sangat perlu proses penanganan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah seperti melakukan pencucian, sortasi/grading dan pengemasan. Dengan perlakuan seperti ini beberapa komoditi bisa dipasarkan pada segmen pasar yang berbeda sehingga bisa diperoleh tingkat keuntungan yang lebih besar. Pada industri pengolahan perlu perlakuan untuk memperpanjang daya simpan bahan segar seperti pendinginan, pengeringan dll. Produk pertanian yang dipasarkan dalam keadaan segar biasanya yang berkualitas baik sementara yang berkualitas kurang baik diolah menjadi aneka jenis makanan/minuman. Selain itu pengolahan juga bisa dilakukan terhadap produk yang terlalu banyak jumlahnya, akan tetapi perlu memperkirakan jumlah produksi untuk mengantisipasi kurangnya bahan baku pada kondisi tertentu.2. Musiman Kebanyakan produk pertanian tidak dapat diproduksi pada setiap saat dan pada setiap tempat sehingga perlu penanganan khusus pada saat panen melimpah dan sebaliknya juga perlu langkah antisipatif pada saat produksi menurun. Hal ini sangat mempengaruhi harga jual produk pertanian tersebut. Untuk industri produk olahan perlu membuat perkiraan daya serap pasar sehingga bisa direncanakan jumlah produksi pada saat panen melimpah guna mengantisipasi penurunan pasokan bahan pada saat jumlah panen menurun.3. Volume besar Umumnya produk pertanian mempunyai volume yang besar, untuk itu perlu penanganan seperti pengeringan, sortasi dan pengolahan untuk mengatasinya. Industri pengolahan merupakan salah satu langkah yang tepat guna memperoleh nilai tambah selain untuk mengatasi penjualan produk segar yang volumenya relatif besar.III. PENERAPAN MANAJEMEN AGRIBISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN Dalam berwirausaha pada sektor pertanian sangat diperlukan perhitungan yang cermat guna melakukan berbagai langka antisipatif agar terhindar dari resiko kerugian. Untuk itu diperlukan memperhatkan beberapa hal berikut ini :1. KETERSEDIAAN ABAHAN BAKU Berwirausaha pada industri pengolahan produk pertanian harus selalu memperhatikan ketersediaan bahan baku yang meliputi mutu, jumlah dan kontinyuitas. Sebelum memulai usaha sangat perlu memperhatikan ketersediaan bahan baku. Bahan baku yang tidak terjamin ketersediaannya akan mengganggu proses produksi sedangkan mutu bahan baku yang tidak stabil akan menurunkan mutu produk olahan yang dihasilkan2. PEMASARAN Pada saat ini permintaan pasar untuk berbagai produk olahan cukup tinggi namun memang sangat diperlukan kejelian produsen dalam hal pemasaran. Kegiatan usaha yang dikordinir dalam suatu kelompok akan lebih mampu menembus pasar bila dibandingkan dengan usaha perseorangan. Namun demikian kelompok usaha ini harus mampu menciptakan manajemen usaha yang baik sehingga keuntungan dapat dinikmati oleh semua anggota kelompok secara wajar. Semua produk yang akan dipasarkan harus memperhatikan beberapa hal berikut ini : Permintaan pasar Penentuan jenis produk yang dihasilkan harus berdasarkan permintaan pasar, hal ini bisa diketahui dengan cara melihat beberapa toko untuk melihat dan mengetahui produk apa yang banyak terjual. Selain itu bisa juga diamati minat konsumen secara langsung di pasaran. Persaingan Pasar Dalam berwirausaha setiap produsen harus siap untuk bersaing dengan produsen lainnya. Untuk bersaing dan memenangkan persaingan perlu dikaji kelebihan produk lain agar kita minimal bisa mengimbanginya sehingga tidak ditinggalkan oleh konsumen. Persaingan pasar antara lain dipengaruhi oleh harga,mutu dan tampilan produk. Untuk itu kebersihan produk dan penampilan kemasan seringkali menjadi perhatian utama bagi konsumen. Perkembangan/tren pasar Saat sekarang pasar sangat dinamis, produk yang mengusai pasar seringkali berubah dari waktu kewaktu, kecuali beberapa produk yang sudah dikenal sebagai produk spesifik dari suatu daerah. Agar kita tidak tertinggal oleh produsen lainnya maka perkembangan/tren pasar ini harus selalu dicermati. Perubahan selera konsumen Selera konsumen juga bisa mengalami perubahan, hal ini antara lain disebabkan oleh promosi produk tertentu, tingkat pendapatan masyarakat, kesadaran terhadap kesehatan, dan kejadian-kejadian khusus di tengah-tengah masyarakat misalnya berita tentang penggunaan formalin dan bahan berbahaya lainnya. Namun demikian perubahan selera konsumen ini ada yang sifatnya permanen dan ada yang hanya sesaat saja. Perubahan selera konsumen ini ada kalanya menjadi hambatan/tantangan namun demikian bisa juga menjadi suatu peluang bagi produsen yang kreatif.3. TEKNOLOGI PENGOLAHAN Teknologi pengolahan hasil pertanian sudah sangat berkembang, untuk itu perlu dipilih teknologi yang tidak memerlukan peralatan yang mahal, sesuai dengan kondisi yang diperlukan, proses pengolahan mudah dilakukan dan biaya produksinya juga relatif rendah. Dalam pemilihat alat juga harus diperhatikan kapasitas alat, spesifikasi teknis seperti daya listrik dsb. Dalam pemilihan teknologi juga harus diupayakan pengolahan yang bisa memanfaatkan limbah menjadi produk yang bisa dipasarkan. Pada proses pengolahan perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini : Pengendalian mutu : Proses pengendalian mutu sangat diperlukan untuk menghasilkan produk yang mempunyai daya saing tinggi, untuk itu perlu diperhatikan hal berikut ini : Standarisasi bahan baku/bahan mentah Standarisasi Proses Pengolahan Standarisasi alat/mesin pengolahan Kelas mutu Masa kadaluarsa Pengemasan ( Pembotolan, Pengalengan, Pembungkusan dll ) Penyimpanan produk akhir yang antara lain meliputi meliputi cara penumpukan, penyinaran, kelembaban, suhu, lama penyimpanan dll.4. TENAGA KERJAPengelolaan tenaga kerja merupakan salah satu hal yang sangat menentukan tingkat efisiensi biaya produksi. Dalam agribisnis harus bisa ditentukan dengan tepat tingkat kemampuan/ketrampian yang harus dimiliki oleh tenaga kerja yang digunakan selain itu juga harus dihitung dengan cermat jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan serta pembagian kerjanya. Pada industri makanan saat ini bila jumlah penjualan perhari masih dibawah Rp. 500.000,- maka usaha tersebut sebaiknya hanya dikerjakan oleh anggota keluarga saja karena secara ekonomis belum layak untuk mengeluarkan gaji untuk tenaga kerja tambahan yang diupah.5. MODAL USAHA Untuk memulai usaha sangat perlu mempertimbangkan modal usaha yang diperlukan. Dalam hal ini sangat perlu memulai usaha dengan menggunakan modal sendiri atau modal kelompok, sebisa mungkin harus dihindari menggunakan modal berupa pinjaman. Selain itu dalam memulai produksi juga harus dipertimbangkan biaya produksi untuk beberapa kali proses produksi, hal ini disebabkan karena suatu usaha baru dalam waktu tertentu belum akan memperolah keuntungan yang tetap sehingga diperlukan ketersediaan modal usaha.6. MANAJEMEN Dalam mengelola usaha perlu diperhatikan masalah manajemen usaha. Hal ini dilakukan agar suatu usaha terkelola dengan baik. Manajemen perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana, proses produksi, tenaga kerja dan pemasaran. Dengan manajemen yang baik suatu usaha dapat dikembangkan dengan baik sehingga bisa melakukan pengembangan usaha sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Semua kegiatan harus terdokumentasi (tercatat) dengan baik, pencatatan harus dilakukan secara teratur terhadap semua bentuk kegiatan. Keuangan harus dibukukan secara teratur sehingga semua pemasukan dan pengeluaran bisa dievaluasi dengan baik. Dalam berbisnis bila produk yang dihasilkan lebih dari satu jenis maka harus ditentukan produk mana yang akan dijadikan sebagai bisnis utama. Hal ini sangat perlu karena setiap usaha harus berupaya untuk menciptakan brand image yang baik, dan itu hanya bisa diperoleh bila ada produk yang diunggulkan. Untuk itu pada perencanaan usaha harus dibuat tahapan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembentukan brand image tersebut. Brand image ini selain berkaitan dengan mutu produk juga berkaitan dengan harga jual. Dalam menentukan harga jual harus diperhitungkan beberapa hal berikut ini : Biaya produksi, termasuk biaya investasi serta biaya penyusutan bangunan dan alat/mesin yang digunakan. Harga jual produk pesaing Tingkat kerusakan barang/yang tidak terjual (pada produk baru khususnya untuk makanan basah/semi basah biasanya sekitar 30 persen tidak terjual) Daya beli masyarakat Tingkat keuntungan yang diharapkan7. PENGEMBANGAN USAHABagi usaha yang sudah mapan diperlukan pengembangan usaha agar konsumen tidak jenuh dan keuntungan bisa ditingkatkan. Pengembangan usaha bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut : SimplifikasiYang dilakukan adalah penyederhanaan produk, misalnya pada saat terjadinya kenaikan biaya produksi maka pengembangan usaha dilakukan antara lain dengan cara pengecilan ukuran produk, penyederhanaan kemasan, perubahan bentuk dsb. DiversifikasiPada kondisi ini yang dilakukan adalah pembuatan produk baru, hal ini dilakukan bila produk lama sudah jenuh sehingga tidak bisa lagi ditingkatkan jumlah produksinya. Sebaiknya produk baru ini bisa diolah dengan menggunakan alat/mesin yang sudah ada dan bahan bakunya juga tidak berbeda jauh dengan produk yang sudah ada StandarisasiDalam hal ini yang dilakukan adalah penyeragaman produk baik dari segi bentuk, ukuran, penampilan dan rasa. Untuk itu diperlukan membuat standar pengolahan produk mulai dari standar bahan baku, proses pengolahan dst. .MANAJEMEN AGRIBISNIS DAN KEWIRAUSAHAANOleh: Ir. Gunarif Taib, M.Si. I. PERANAN SEKTOR PERTANIAN Penduduk Sumatera Barat berjumlah 4,6 juta jiwa atau 1,1 juta KK (Kepala Keluarga) dan 60 persen diantaranya (640.000 KK) bergerak dalam sektor pertanian. Kalau dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat Tahun 2006 maka sektor petanian hanya memberikan kontribusiya 25,26 persen yang terdiri dari tanaman pangan 13,11%, perkebunan 5,60%, peternakan 2,04%, kehutanan 1,50%, dan perikanan 3,01%. Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian ini diperlukan terobosan antara lain berupa upaya peningkatan efisiensi biaya produksi dan mengusahakan adanya nilai tambah melalui proses penanganan dan pengolahan hasil produk pertanian. Peningkatan efisiensi biaya produksi bisa dicapai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien, untuk itu aspek manajerial dalam usaha tani perlu mendapat perhatian selain dari upaya penerapan teknologi. Proses nilai tambah bisa diperoleh melalui penanganan pada pasca panen seperti melakukan sortasi/grading dan pengemasan sehingga harga jual bisa ditingkatkan. Selain itu juga bisa dilakukan pengolahan bahan segar menjadi produk olahan yang mempunyai prospek pasar cukup baik. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam berwirausaha pada sektor pertanian khususnya dalam penanganan dan pengolahan hasil tersebut perlu diperhatikan aspek manajemen dalam pemanfaatan sumberdaya yang ada. Saat ini wirausaha di sektor pertanian umumnya dikuasai oleh pedagang sehingga petani hanya diposisikan sebagai penerima harga sedangkan penentuan harga berada di tangan pedagang. Hal ini sangat merugikan petani karena keuntungan terbesar sesungguhnya berada pada tata niaga/pemasaran dan industri pengolahan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan pemberdayaan petani untuk bisa bergerak pada rantai tata niaga dan industri pengolahan. Upaya ini akan sulit dilakukan bila petani bergerak secara perorangan sehingga diperlukan pembentukan kelompok yang solid. Dalam kegiatan kelompok perlu diperhatikan aspek manajemen sehingga kelompok tersebut mempunyai perencanaan yang baik, mampu melakukan evaluasi dengan tepat dan semua kegiatan terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian diharapkan kelompok bisa berkembang dengan cepat dan keuntungan secara ekonomis bisa diperoleh. Dalam pengelolaan kegiatan agribisnis juga perlu diperhatikan karakteristik komoditi pertanian yang sangat spesifik untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian dalam berusaha. II. KARAKTERISTIK PRODUK PERTANIAN Manajemen Agribisnis merupakan bagian dari ilmu manajemen yang spesifik karena berhadapan dengan produk pertanian yang mempunyai sifat khusus sebagai berikut : 1. Mudah rusak Produk pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura sangat mudah rusak sehingga harus segera dipasarkan atau diolah menjadi produk olahan. Dalam hal ini bila produk akan dipasarkan dalam bentuk segar maka sangat perlu proses penanganan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah seperti melakukan pencucian, sortasi/grading dan pengemasan. Dengan perlakuan seperti ini beberapa komoditi bisa dipasarkan pada segmen pasar yang berbeda sehingga bisa diperoleh tingkat keuntungan yang lebih besar. Pada industri pengolahan perlu perlakuan untuk memperpanjang daya simpan bahan segar seperti pendinginan, pengeringan dll. Produk pertanian yang dipasarkan dalam keadaan segar biasanya yang berkualitas baik sementara yang berkualitas kurang baik diolah menjadi aneka jenis makanan/minuman. Selain itu pengolahan juga bisa dilakukan terhadap produk yang terlalu banyak jumlahnya, akan tetapi perlu memperkirakan jumlah produksi untuk mengantisipasi kurangnya bahan baku pada kondisi tertentu. 2. Musiman Kebanyakan produk pertanian tidak dapat diproduksi pada setiap saat dan pada setiap tempat sehingga perlu penanganan khusus pada saat panen melimpah dan sebaliknya juga perlu langkah antisipatif pada saat produksi menurun. Hal ini sangat mempengaruhi harga jual produk pertanian tersebut. Untuk industri produk olahan perlu membuat perkiraan daya serap pasar sehingga bisa direncanakan jumlah produksi pada saat panen melimpah guna mengantisipasi penurunan pasokan bahan pada saat jumlah panen menurun. 3. Volume besar Umumnya produk pertanian mempunyai volume yang besar, untuk itu perlu penanganan seperti pengeringan, sortasi dan pengolahan untuk mengatasinya. Industri pengolahan merupakan salah satu langkah yang tepat guna memperoleh nilai tambah selain untuk mengatasi penjualan produk segar yang volumenya relatif besar. III. PENERAPAN MANAJEMEN AGRIBISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN Dalam berwirausaha pada sektor pertanian sangat diperlukan perhitungan yang cermat guna melakukan berbagai langka antisipatif agar terhindar dari resiko kerugian. Untuk itu diperlukan memperhatkan beberapa hal berikut ini : 1. KETERSEDIAAN ABAHAN BAKU Berwirausaha pada industri pengolahan produk pertanian harus selalu memperhatikan ketersediaan bahan baku yang meliputi mutu, jumlah dan kontinyuitas. Sebelum memulai usaha sangat perlu memperhatikan ketersediaan bahan baku. Bahan baku yang tidak terjamin ketersediaannya akan mengganggu proses produksi sedangkan mutu bahan baku yang tidak stabil akan menurunkan mutu produk olahan yang dihasilkan 2. PEMASARAN Pada saat ini permintaan pasar untuk berbagai produk olahan cukup tinggi namun memang sangat diperlukan kejelian produsen dalam hal pemasaran. Kegiatan usaha yang dikordinir dalam suatu kelompok akan lebih mampu menembus pasar bila dibandingkan dengan usaha perseorangan. Namun demikian kelompok usaha ini harus mampu menciptakan manajemen usaha yang baik sehingga keuntungan dapat dinikmati oleh semua anggota kelompok secara wajar. Semua produk yang akan dipasarkan harus memperhatikan beberapa hal berikut ini : Permintaan pasar Penentuan jenis produk yang dihasilkan harus berdasarkan permintaan pasar, hal ini bisa diketahui dengan cara melihat beberapa toko untuk melihat dan mengetahui produk apa yang banyak terjual. Selain itu bisa juga diamati minat konsumen secara langsung di pasaran. Persaingan Pasar Dalam berwirausaha setiap produsen harus siap untuk bersaing dengan produsen lainnya. Untuk bersaing dan memenangkan persaingan perlu dikaji kelebihan produk lain agar kita minimal bisa mengimbanginya sehingga tidak ditinggalkan oleh konsumen. Persaingan pasar antara lain dipengaruhi oleh harga,mutu dan tampilan produk. Untuk itu kebersihan produk dan penampilan kemasan seringkali menjadi perhatian utama bagi konsumen. Perkembangan/tren pasar Saat sekarang pasar sangat dinamis, produk yang mengusai pasar seringkali berubah dari waktu kewaktu, kecuali beberapa produk yang sudah dikenal sebagai produk spesifik dari suatu daerah. Agar kita tidak tertinggal oleh produsen lainnya maka perkembangan/tren pasar ini harus selalu dicermati. Perubahan selera konsumen Selera konsumen juga bisa mengalami perubahan, hal ini antara lain disebabkan oleh promosi produk tertentu, tingkat pendapatan masyarakat, kesadaran terhadap kesehatan, dan kejadian-kejadian khusus di tengah-tengah masyarakat misalnya berita tentang penggunaan formalin dan bahan berbahaya lainnya. Namun demikian perubahan selera konsumen ini ada yang sifatnya permanen dan ada yang hanya sesaat saja. Perubahan selera konsumen ini ada kalanya menjadi hambatan/tantangan namun demikian bisa juga menjadi suatu peluang bagi produsen yang kreatif. 3. TEKNOLOGI PENGOLAHAN Teknologi pengolahan hasil pertanian sudah sangat berkembang, untuk itu perlu dipilih teknologi yang tidak memerlukan peralatan yang mahal, sesuai dengan kondisi yang diperlukan, proses pengolahan mudah dilakukan dan biaya produksinya juga relatif rendah. Dalam pemilihat alat juga harus diperhatikan kapasitas alat, spesifikasi teknis seperti daya listrik dsb. Dalam pemilihan teknologi juga harus diupayakan pengolahan yang bisa memanfaatkan limbah menjadi produk yang bisa dipasarkan. Pada proses pengolahan perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini : Pengendalian mutu : Proses pengendalian mutu sangat diperlukan untuk menghasilkan produk yang mempunyai daya saing tinggi, untuk itu perlu diperhatikan hal berikut ini : Standarisasi bahan baku/bahan mentah Standarisasi Proses Pengolahan Standarisasi alat/mesin pengolahan Kelas mutu Masa kadaluarsa Pengemasan ( Pembotolan, Pengalengan, Pembungkusan dll ) Penyimpanan produk akhir yang antara lain meliputi meliputi cara penumpukan, penyinaran, kelembaban, suhu, lama penyimpanan dll. 4. TENAGA KERJA Pengelolaan tenaga kerja merupakan salah satu hal yang sangat menentukan tingkat efisiensi biaya produksi. Dalam agribisnis harus bisa ditentukan dengan tepat tingkat kemampuan/ketrampian yang harus dimiliki oleh tenaga kerja yang digunakan selain itu juga harus dihitung dengan cermat jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan serta pembagian kerjanya. Pada industri makanan saat ini bila jumlah penjualan perhari masih dibawah Rp. 500.000,- maka usaha tersebut sebaiknya hanya dikerjakan oleh anggota keluarga saja karena secara ekonomis belum layak untuk mengeluarkan gaji untuk tenaga kerja tambahan yang diupah. 5. MODAL USAHA Untuk memulai usaha sangat perlu mempertimbangkan modal usaha yang diperlukan. Dalam hal ini sangat perlu memulai usaha dengan menggunakan modal sendiri atau modal kelompok, sebisa mungkin harus dihindari menggunakan modal berupa pinjaman. Selain itu dalam memulai produksi juga harus dipertimbangkan biaya produksi untuk beberapa kali proses produksi, hal ini disebabkan karena suatu usaha baru dalam waktu tertentu belum akan memperolah keuntungan yang tetap sehingga diperlukan ketersediaan modal usaha. 6. MANAJEMEN Dalam mengelola usaha perlu diperhatikan masalah manajemen usaha. Hal ini dilakukan agar suatu usaha terkelola dengan baik. Manajemen perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana, proses produksi, tenaga kerja dan pemasaran. Dengan manajemen yang baik suatu usaha dapat dikembangkan dengan baik sehingga bisa melakukan pengembangan usaha sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Semua kegiatan harus terdokumentasi (tercatat) dengan baik, pencatatan harus dilakukan secara teratur terhadap semua bentuk kegiatan. Keuangan harus dibukukan secara teratur sehingga semua pemasukan dan pengeluaran bisa dievaluasi dengan baik. Dalam berbisnis bila produk yang dihasilkan lebih dari satu jenis maka harus ditentukan produk mana yang akan dijadikan sebagai bisnis utama. Hal ini sangat perlu karena setiap usaha harus berupaya untuk menciptakan brand image yang baik, dan itu hanya bisa diperoleh bila ada produk yang diunggulkan. Untuk itu pada perencanaan usaha harus dibuat tahapan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembentukan brand image tersebut. Brand image ini selain berkaitan dengan mutu produk juga berkaitan dengan harga jual. Dalam menentukan harga jual harus diperhitungkan beberapa hal berikut ini : Biaya produksi, termasuk biaya investasi serta biaya penyusutan bangunan dan alat/mesin yang digunakan. Harga jual produk pesaing Tingkat kerusakan barang/yang tidak terjual (pada produk baru khususnya untuk makanan basah/semi basah biasanya sekitar 30 persen tidak terjual) Daya beli masyarakat Tingkat keuntungan yang diharapkan 7. PENGEMBANGAN USAHA Bagi usaha yang sudah mapan diperlukan pengembangan usaha agar konsumen tidak jenuh dan keuntungan bisa ditingkatkan. Pengembangan usaha bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Simplifikasi Yang dilakukan adalah penyederhanaan produk, misalnya pada saat terjadinya kenaikan biaya produksi maka pengembangan usaha dilakukan antara lain dengan cara pengecilan ukuran produk, penyederhanaan kemasan, perubahan bentuk dsb. Diversifikasi Pada kondisi ini yang dilakukan adalah pembuatan produk baru, hal ini dilakukan bila produk lama sudah jenuh sehingga tidak bisa lagi ditingkatkan jumlah produksinya. Sebaiknya produk baru ini bisa diolah dengan menggunakan alat/mesin yang sudah ada dan bahan bakunya juga tidak berbeda jauh dengan produk yang sudah ada Standarisasi Dalam hal ini yang dilakukan adalah penyeragaman produk baik dari segi bentuk, ukuran, penampilan dan rasa. Untuk itu diperlukan membuat standar pengolahan produk mulai dari standar bahan baku, proses pengolahan dst. .20AUGMANAJEMEN KELEMBAGAANPosted by gunariftaib inUncategorized. Leave a CommentSISTEM MANAJEMEN KELEMBAGAAN PADA KELOMPOK USAHADI KABUPATEN AGAMBerbagai kelompok usaha sudah mulai berkembang di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Agam. Perkembangan masing-masing lembaga dipengaruhi oleh kondisi wilayah terutama potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Kabupaten Agam sebagai salah satu daerah yang menjadi tujuan wisata di Prop Sumbar mempunyai prospek yang sangat baik untuk dikembangkan.Kelembagaan dibutuhkan untuk mengorganisir berbagai kegiatan, termasuk dalam industri pengolahan hasil pertanian sehingga diperoleh hasil optimal dengan memperhatikan tingkat efisiensi dalam berproduksi. Pada tingkat kelompok usaha kelembagaan sangat diperlukan terutama dalam merancang kegiatan yang didasari oleh kepentingan bersama dan demi kemajuan bersama.MANAJEMEN KELEMBAGAANKelembagaan perlu dikelola dengan baik agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Pada industri pengolahan hasil pertanian biasanya dibentuk Kelompok Usaha, bila usaha dilakukan dalam kelompok maka diperlukan aturan yang dirancang bersama sehingga seluruh anggota memahami perannya masing-masing. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada manajemen kelembagaan kelompok usaha antara lain adalah sebagai berikut:1. Pemanfaatan potensi anggotaDalam hal ini sumberdaya manusia yang beragam baik dari segi keterampilan maupun pendidikannya harus dapat dimanfaatkan sesuai dengan potensinya masing-masing.2. Pemanfatan sumberdaya lokalDengan melakukan kegiatan usaha yang melembaga maka harus diperhatikan potensi sumberdaya lokal. Dalam hal ini penggunaan sumberdaya lokal secara optimal dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi3. Pemerataan kegiatan dalam kelompok.Dengan adanya kelembagaan maka dapat dibuat segala ketentuan sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam hal ini dapat diatur hak dan kewajiban setiap anggota sehingga setiap anggota dapat mengeksprsikan dirinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.4. Pembagian keuntungan secara wajar.Semua anggota memperoleh hak sesuai dengan tingkat partisipasinya dalam kelompok. Hal ini memudahkan dalam pengelolaan usaha termasuk dalam hal pembagian keuntungan masing-masing anggota.5. Mencari terobosan pasarDalam berproduksi maka kelompok usaha harus berorientasi terhadap pasar, khususnya pasaran lokal. Jenis produk yang diproduksi harus disesuaikan dengan kecenderungan pasar yang sangat dinamis.KELOMPOK USAHA DI KABUPATEN AGAMKabupaten agam merupakan salah satu daerah yang sangat potensial untuk berwirausaha. Selain daerahnya yang subur sehingga banyak bahan baku yang dapat diolah, pemasaran hasil olahannyapun dapat dilakukan dengan relatif mudah. Untuk itu perlu doperhatikan beberapa hal berikut ini :1. Pemilihan produk olahan yang tepatProduk olahan yang sudah banyak dipasarkan antara lain keripik sanjai, keripik balado dll. Untuk diversifikasi produk guna mengantisipasi kejenuhan pasar maka harus diusahakan pengolahan produk yang berbahan baku ubi jalar, kacang tanah, ubi kayu, kentang dll. Komoditi ini sangat banyak dibudidayakan di daerah Kabupaten Agam sehingga perlu dikembangkan pada masa yang akan datang.2. Penetepan daerah pemasaranKabupaten Agam dan Bukittinggi merupakan pasar lokal yang sangat baik, selain itu Kabupaten Agam juga berada di bagian tengah dari Prop Sumbar sehingga mempunyai akses yang baik terhadap Kota Padang, Pekan Baru dan Medan. Hal ini perlu dimanfaatkan untuk pemasaran produk olahan hasil pertanian dari kab Agam.3. Pembenahan kelompok usahaUntuk melakukan usaha dalam skala ekonomis maka perlu pembenahan kelompok usaha. Hal ini terutama diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen produksi dan pemasaran.BEBERAPA HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN :Usaha industri pengolahan hasil pertanian yang dikelola oleh kelompok usaha atau lembaga lainnya di tingkat pedesaan memerlukan penanganan yang berbeda bila dibandingkan dengan usaha yang dikelola oleh perseorangan. Untuk itu waktu memulai usaha perlu diperhatikan hal berikut ini :1. Jenis industri olahan yang dipilihIndustri olahan yang dipilih haruslah industri olahan yang dapat diproduksi secara massal dan tidak memerlukan peralatan yang spesifik. Hal ini disebabkan karena industri olahan oleh kelompok tani diharapkan dapat memanfaat tenaga kerja lokal secara maksimal.2. Struktur organisasiMasing-masing industri pengolahan akan membutuhkan struktur organisasi yang berbeda sesuai dengan skala usaha dan jenis usaha yang dilakukan. Dalam menentukan struktur organisasi harus dipikirkan agar struktur yang ada dapat berjalan dengan efisien dan efektif, untuk itu perlu diperhatikan hal berikut ini :- Jumlah jabatan sesuai dengan kebutuhan.- Pembagian tugas yang jelas dan tegas.- Penerapan sanksi yang tegas bagi yang melanggar ketentuan dan penghargaan bagi yang berprestasi lebih.- Memperhatikan struktur sosial masyarakat setempatURUTAN KEGIATAN PRODUKSI1. PerencanaanPerencanaan produksi disusun secara bersama dengan memperhatikan berbagai hal sebagai berikut :- Daya serap pasar- Ketersediaan bahan baku- Ketersediaan modal usaha- Ketersediaan tenaga kerja- Peralatan produksi yang adaPerencanaan sangat diperlukan dalam suatu kegiatan, tanpa ada perencanaan maka pelaksanaan tidak mempunyai acuan yang jelas, tidak ada dasar dalam melakukan evaluasi sehingga tidak dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.2. PelaksanaanYang dilaksanakan dalam suatu proses produksi adalah apa yang telah direncanakan. Dalam hal ini perlu diperhatikan waktu produksi yang tepat serta proses produksi yang benar.3. EvaluasiSuatu lembaga harus mampu melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan perencanaan sebagai acuan utama. Kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan perlu dievaluasi apakah sudah terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan. Seandainya belum terlaksana maka harus dicari penyebabnya untuk dicarikan pemecahan masalahnya.4. PerbaikanHasil evaluasi perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan. Perbaikan yang dilakukan harus mengacu pada apa yang belum terlaksana seperti yang direncanakan. Langkah perbaikan harus dilaksanakan tepat waktu. Dalam melaksanakan perbaikan harus dilakukan perbaikan terhadap permasalahan yang sangat mendasar sehingga perbaikan yang dilakukan dapat memberikan hasil yang optimal.MANFAAT KELEMBAGAAN DALAM BERPRODUKSIDalam berusaha terdapat dua pilihan pengelolaan yaitu usaha perseorangan dan kelompok. Beberapa manfaat dari kelompok usaha antara lain adalah :1. Memudahkan pemasaranKelompok Usaha lebih mudah memasarkan produksinya karena jumlah produksi lebih banyak dan kontinyuitasnya lebih terjamin. Hal ini merupakan salah satui syarat mutlak dalam pemasaran yang baik2. Efisiensi lebih tinggiKelompok usaha lebih mudah mencapai efisiensi baik dalam berproduksi maupun pemasaran. Hal ini karena skala usaha relatif besar dan lebih terbuka terhadap adaptasi teknologi.3. Skala usaha lebih ekonomisPenggabunga usaha menjadi kelompok usaha tentu akan meningkatkan skala usaha menjadi lebih ekonomis. Hal ini relatif sulit terjadi bila usaha dilakukan secara perseorangan.
Agroindustriadalah kegiatan yang memanfaatkan hasilpertaniansebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan sertajasauntuk kegiatan tersebut[1]. Secara eksplisit pengertian Agroindustri pertama kali diungkapkan oleh Austin (1981)[2]yaitu perusahaan yang memproses bahan nabati (yang berasal daritanaman) atauhewani(yang dihasilkan oleh hewan). Proses yang digunakan mencakup pengubahan dan pengawetan melalui perlakuanfisikataukimiawi, penyimpanan,pengemasandandistribusi. Produk Agroindustri ini dapat merupakan produk akhir yang siap dikonsumsi ataupun sebagai produk bahan bakuindustrilainnya.Agroindustri merupakan bagian dari kompleks industri pertanian sejak produksi bahan pertanian primer, industri pengolahan atau transformasi sampai penggunaannya oleh konsumen[3]. Agroindustri merupakan kegiatan yang saling berhubungan (interlasi)produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pendanaan,pemasarandandistribusiprodukpertanian[4]. Dari pandangan para pakarsosialekonomi, agroindustri (pengolahan hasilpertanian) merupakan bagian dari lima subsistemagribisnisyang disepakati, yaitu subsistem penyediaan saranaproduksidan peralatan. usaha tani, pengolahan hasil,pemasaran, sarana dan pembinaan[5]. Agroindustri dengan demikian mencakupIndustriPengolahan HasilPertanian(IPHP), Industri Peralatan DanMesinPertanian (IPMP) dan IndustriJasaSektorPertanian(IJSP).Industri Pengolahan Hasil Pertanian (IPHP) dapat dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:1. IPHPTanamanPangan, termasuk di dalamnya adalah bahanpangankayakarbohidrat,palawijadan tanamanhortikultura.2. IPHP TanamanPerkebunan, meliputitebu,kopi,teh,karet,kelapa,kelapa sawit,tembakau,cengkeh,kakao,vanili,kayu manisdan lain-lain.3. IPHP Tanaman HasilHutan, mencakup produkkayuolahan dan non kayu sepertidamar,rotan,tengkawangdan hasil ikutan lainnya.4. IPHPPerikanan, meliputi pengolahan dan penyimpananikandan hasillautsegar,pengalengandan pengolahan, serta hasil sampingikandanlaut.5. IPHPPeternakan, mencakup pengolahandagingsegar,susu,kulit, dan hasil samping lainnya.Industri Peralatan danMesinPertanian(IPMP) dibagi menjadi dua kegiatan sebagai berikut:1. IPMP BudidayaPertanian, yang mencakupalatdanmesinpengolahanlahan(cangkul,bajak,traktordan lain sebagainya).2. IPMP Pengolahan, yang meliputi alat dan mesin pengolahan berbagai komoditaspertanian, misalnya mesin perontokgabah, mesin penggilinganpadi, mesin pengering dan lain sebagainya.Industri Jasa Sektor Pertanian (IJSP) dibagi menjadi tiga kegiatan sebagai berikut:1. IJSP Perdagangan, yang mencakup kegiatan pengangkutan, pengemasan serta penyimpanan baik bahan baku maupun produk hasil industri pengolahanpertanian.2. IJSP Konsultasi, meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan mutu serta evaluasi dan penilaian proyek.3. IJSP Komunikasi, menyangkut teknologi perangkat lunak yang melibatkan penggunaankomputerserta alatkomunikasimodern lainya.Dengan pertanian sebagai pusatnya, agroindustri merupakan sebuah sektorekonomiyang meliputi semua perusahaan, agen dan institusi yang menyediakan segala kebutuhanpertaniandan mengambil komoditas daripertanianuntuk diolah dan didistribusikan kepadakonsumen[6]. Nilai strategis agroindustri terletak pada posisinya sebagaijembatanyang menghubungkan antar sektorpertanianpada kegiatan hulu dan sektor industri pada kegiatan hilir. Dengan pengembangan agroindustri secara cepat dan baik dapat meningkatkan, jumlah tenaga kerja, pendapatanpetani, volumeekspordandevisa, pangsapasardomestik daninternasional, nilai tukar produk hasil pertanian dan penyediaanbahan bakuindustri[3].Daftar isi[sembunyikan] 1Penerapan teknologi untuk agroindustri 1.1Contoh penerapan teknologi untuk produk agroindustri 2Pengembangan agroindustri 3RujukanPenerapan teknologi untuk agroindustri[sunting|sunting sumber]
proses pengolahan lanjut pada kegiatan agroindustriSalah satu kendala dalam pengembangan agroindustri diIndonesiaadalah kemampuan mengolahprodukyang masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian besar komoditas pertanian yang diekspor merupakanbahanmentah dengan indeks retensi pengolahan sebesar 71-75%. Angka tersebut menunjukkan bahwa hanya 25-29% produk pertanian Indonesia yang diekspor dalam bentuk olahan. Kondisi ini tentu saja memperkecil nilai tambah yang yang diperoleh darieksporprodukpertanian, sehingga pengolahan lebih lanjut menjadi tuntutan bagi perkembangan agroindustri di era global ini. Teknologi yang digolongkan sebagai teknologi agroindustri produk pertanian begitu beragam dan sangat luas mencakupteknologipascapanen dan teknologi proses. Untuk memudahkan, secara garis besar teknologi pascapanen digolongkan berdasarkan tahapannya yaitu, tahap atau tahap sebelum pengolahan, tahap pengolahan dan tahap pengolahan lanjut[6]. Perlakuan pascapanen tahap awal meliputi, pembersihan,pengeringan, sortasi dan pengeringan berdasarkan mutu, pengemasan,transportdan penyimpanan, pemotongan/pengirisan, penghilanganbiji, pengupasan dan lainnya. Perlakuan pascapanen tahap pengolahan antara lain,fermentasi,oksidasi,ekstraksibuah,eks