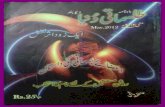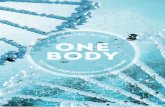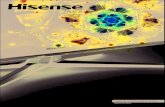Perdarahan Pasca Salin-Nurse May 2011.pdf
-
Upload
ino-da-conceicao -
Category
Documents
-
view
28 -
download
0
Transcript of Perdarahan Pasca Salin-Nurse May 2011.pdf
-
Tatalaksana Pre Hospital Perdarahan Pasca Salin Oleh : Muhammad Ardian, dr, SpOG Disampaikan pada seminar : Recent Management and Technique Emergency case pre hospital care 4 Juli 2011 Latar belakang Setiap harinya 1500 wanita meninggal oleh karena kehamilan. Pada tahun
2005 diperkirakan 536 000 ibu meninggal seluruh dunia. Sebagian besar
kematian tersebut terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang, dan
umumnya kematian tersebut bisa dihindari. (WHO, UNICEF, UNFPA, world
bank, 2007)
Menurut Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), AKI menurun dari 450
per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1986 menjadi 425 per 100.000
kelahiran hidup pada tahun 1992, kemudian menurun lagi menjadi 373 per
100.000 kelahiran hidup pada tahun 1995. Pada tahun 2002-2003 AKI
sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup diperoleh dari hasil SDKI. Hal ini
menunjukkan AKI cenderung terus menurun. Tetapi bila dibandingkan dengan
target yang ingin dicapai secara nasional pada tahun 2010, yaitu sebesar 125
per 100.000 kelahiran hidup, maka apabila penurunannya masih seperti
tahun-tahun sebelumnya, diperkirakan target tersebut di masa mendatang
sulit tercapai.(Depkes RI, 2007; Saifudin AB, 2005).
Angka kematian ibu di Inonesia tergolong masih tinggi, AKI Indonesia 65 kali
angka kematian ibu di Singapura, 9,5 kali angka kematian ibu di Malaysia dan
2,5 kali angka kematian ibu di Philipina
Seperti yang telah banyak diketahui bahwa perdarahan, eklamsia, komplikasi
abortus, infeksi dan persalinan lama masih menjadi kontributor utama
penyebab kematian ibu (WHO, UNICEF, UNFPA, world bank, 2007).Dan
lebih dari 125.000 kematian maternal (25 33 %) disebabkan karena
perdarahan pasca persalinan (Yasmin, 2003; Hamami, 2005; Miller, 2004;
Khadem, 2007).
-
Definisi HPP Perdarahan pasca salin secara klinik didefinisikan sebagai perdarahan masif
pasca salin sehingga timbul gejala-gejala seperti pusing, lemah, palpitasi,
gelisah, keringat dingin, bingung, sesak sampai dengan pingsan dan / atau
didapatkan tanda-tanda hipovolemia seperti hipotensi, takikardi, oligouri dan
saturasi < 95 %. Perdarahan dapat berasal dari vagina tetapi juga dapat
berasal dari abdomen setelah persalinan sesar atau hematoma pada ligamen
latum. Diagnosis yang akurat dari perdarahan pasca salin sangat penting
untuk memulai suatu intervensi (misal : obat uterotonika, pembedahan, kasus
rujukan) dan berpengaruh terhadap outcome / hasil pengobatan. (Yiadom,
2010; Jacob, 2010).
Definisi yang paling umum (WHO) adalah perdarahan lebih dari 500 ml pasca
salin pervaginam atau perdarahan lebih dari 1000 ml pasca salin sesar. Hal
ini kadang membuat klinisi menjadi under estimate atau over estimate tentang
perdarahan yang terjadi. ( Yiadom, 2010; Jacob, 2010)
Berdasarkan waktu kejadian, perdarahan pasca salin dibagi menjadi dua :
(Jacob, 2010)
- Perdarahan pasca salin primer (early hemorrhage post partum)
yaitu perdarahan terjadi dalam waktu 24 jam setelah persalinan.
- Perdarahan pasca salin sekunder (late hemorrhage post partum)
yaitu perdarahan terjadi setelah 24 jam sampai dengan 12
minggu setelah persalinan.
Insiden Angka kejadian perdarahan pasca salin bervariasi, yaitu sekitar 1 5 % dari
persalinan. Dari data di Amerika Serikat tahun 1994 2006 berkisar antara
2,3 2,6 %, dengan kecenderungan yang semakin meningkat. Atonia uteri
menjadi penyebab yang terbanyak dengan insiden 1,6 2,4 % dari total
persalinan. (Jacob, 2010)
Etiologi
-
Fisiologi Perdarahan yang terjadi setelah persalinan dikendalikan oleh :
(Jacob, 2010)
1. Kontraksi miometrium sehingga terjadi konstriksi dari pembuluh
darah yang mensuplai plasenta bed. Kontraksi miometrium yang
kurang baik bermanifestasi pada atonia uteri.
2. Faktor lokal hemostasis desidua meliputi faktor jaringan dan tipe 1
plasminogen activator inhibitor. Gangguan hemostasis desidua
berhubungan dengan desidualisasi yang inadekuat (misal :
plasenta akreta).
3. Faktor koagulasi sistemik meliputi trombosit dan faktor pembekuan
darah. Gangguan faktor koagulasi menyebabkan terjadinya rentan
perdarahan.
Etiologi dan faktor resiko perdarahan pasca salin adalah sebagai berikut : (
Yiadom, 2010; Jacob, 2010).
1. Atonia uteri (tone)
Ketiadaan kontraksi miometrium yang efektif pasca salin. Atonia
uteri merupakan penyebab utama perdarahan pasca salin yang
paling sering dengan kejadian paling sedikit 80 % dari seluruh
kasus perdarahan pasca salin. Atonia uteri berhubungan dengan :
Distensi yang berlebihan (kehamilan ganda,
polihidramnion, makrosomia)
Infeksi rahim
Obat relaksan rahim
Uterine fatigue setelah persalinan yang lama atau induksi
persalinan
Sisa plasenta
2. Trauma
Perdarahan pada trauma berasal dari laserasi (perineum,
vagina, cerviks, rahim), insisi (histerotomi, episiotomi) atau
ruptur uterus. Faktor resiko trauma adalah bayi besar,
episiotomi, persalinan pervaginam tindakan operatif dan VBAC
(vaginal delivery after C section).
3. Gangguan pembekuan darah (thrombosis)
-
Rentan perdarahan kongenital maupun yang didapat
berhubungan dengan trombositopenia atau kelainan
hemostasis. pada kasus rentan perdarahan yang didapat
disebabkan oleh preeklampsi berat, sindroma HELLP, solusio
plasenta, kematian janin, emboli air ketuban dan sepsis.
Koagulopati konsumtif (DIC) dapat menyebabkan perdarahan
yang hebat.
4. Jaringan plasenta (tissue)
Perdarahan yang terjadi dapat disebabkan oleh sisa plasenta
atau plasenta akreta. Faktor resiko sisa plasenta adalah bekas
persalinan sesar, persalinan prematur, plasenta yang
multilobus, plasenta akreta dan kala III yang memanjang.
5. Inversi uterus (traction)
Komplikasi Perdarahan pasca salin merupakan penyebab utama morbiditas maternal
yang sering menimbulkan gejala sisa yang menetap, meliputi shock, gagal
ginjal akut dan sindroma akut gagal napas. Sindroma Sheehans (post partum
hypopituitarism) jarang terjadi, tetapi potensial menyebabkan kematian.
Kelenjar pituitari membesar selama kehamilan dan mudah terjadi infark
karena hipovolemi shock. Kerusakan kelenjar pituitary dapat ringan sampai
berat dan berpengaruh terhadap sekresi hormon. Hal yang paling sering
terjadi adalah air susu ibu tidak berproduksi dan amenore atau oligomenore,
tetapi manifestasi hypopituitarism yang lain seperti hipotensi, hiponatremi,
hipotiroid juga dapat terjadi dengan segera atau sampai dengan satu tahun
pasca salin. Jika penderita tetap hipotensi setelah perdarahan diatasi dan
penggantian cairan yang adekuat maka penderita tersebut harus dievaluasi
dan mendapat terapi untuk insufisiensi adrenal, evaluasi hormonal dilakukan
sampai dengan 4 atau 6 minggu pasca salin. (Yiadom, 2010; Jacob, 2010).
Komplikasi yang juga jarang tetapi dapat menyebabkan kematian adalah
abdominal compartment syndrome yaitu disfungsi organ karena tekanan intra
abdomen yang tinggi. Diagnosis ini dapat dipertimbangkan pada penderita
-
dengan perut yang distended dan oligouri progresif yang selanjutnya akan
terjadi kegagalan multi organ. (Jacob, 2010)
Komplikasi yang berhubungan dengan tindakan resusitasi cairan seperti
kelebihan cairan (overload) sampai edema paru dan koagulopati dilusi.
Tindakan transfusi juga mempunyai resiko seperti reaksi alergi, reaksi
demam, reaksi anafilaktik, reaksi akut imun hemolisis, infeksi (hepatitis B dan
HIV) dan reaksi metabolik (hipotermi, hiperkalemi, hipokalsemi dan keracunan
sitrat). Komplikasi yang berhubungan dengan prosedur pembedahan seperti
komplikasi saat pembiusan, perdarahan, infeksi, deep venous thrombosis dan
emboli. (Yiadom, 2010; Jacob, 2010)
Tatalaksana
Tatalaksana pada perdarahan pasca salin berbeda-beda sesuai dengan
penyebab dan jenis persalinan (pervaginam atau perabdominam). Tindakan
tersebut sudah harus mulai dilakukan bahkan saat di rumah atau di
Puskesmas (prehospital care). Terapi perdarahan pasca salin terdiri dari 2
komponen yaitu : (Smith, 2010, Yiadom, 2010) 1. Resusitasi penanganan perdarahan hipovolemik shock
2. Identifikasi dan tatalaksana penyebab perdarahan
Prehospital Care (Yiadom, 2010) Intervensi dilakukan sesuai dengan skala prioritas, airway, breathing dan
circulation yang ditujukan untuk life support.
1. Survei primer dilakukan dengan melihat tanda vital dan
pemeriksaan fisik yang difokuskan pada airway, breathing
(pemberian oksigen) dan circulation (detak jantung, tekanan
darah dan pemeriksaan asal perdarahan).
2. Setelah survey primer selesai segera dilakukan, massase
uterus jika atonia uteri, resusitasi cairan, tampon kasa steril jika
terdapat laserasi perineum.
3. Segera rujuk setelah keadaan umum penderita stabil.
Penatalaksanaan khusus Atonia Uteri
-
Atonia uteri terjadi bila miometrium tidak berkontraksi. Uterus menjadi lunak dan pembuluh
darah pada daerah bekas perlekatan plasenta terbuka lebar. Atonia merupakan penyebab
tersering perdarahan postpartum; sekurang-kurangnya 2/3 dari semua perdarahan
postpartum disebabkan oleh atonia uteri. Upaya penanganan perdarahan postpartum
disebabkan atonia uteri, harus dimulai dengan mengenal ibu yang memiliki kondisi yang
berisiko terjadinya atonia uteri. Kondisi ini mencakup:
1. Hal-hal yang menyebabkan uterus meregang lebih dari kondisi normal seperti pada:
Polihidramnion
Kehamilan kembar
Makrosomi
2. Persalinan lama
3. Persalinan terlalu cepat
4. Persalinan dengan induksi atau akselerasi oksitosin
5. Infeksi intrapartum
6. Paritas tinggi
Jika seorang wanita memiliki salah satu dari kondisi-kondisi yang berisiko ini, maka penting
bagi penolong persalinan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya atoni uteri
postpartum. Meskipun demikian, 20% atoni uteri postpartum dapat terjadi pada ibu tanpa
faktor-faktor risiko ini. Adalah penting bagi semua penolong persalinan untuk mempersiapkan
diri dalam melakukan penatalaksanaan awal terhadap masalah yang mungkin terjadi selama
proses persalinan.
Langkah berikutnya dalam upaya mencegah atonia uteri ialah melakukan penanganan kala
tiga secara aktif, yaitu:
1. Menyuntikan Oksitosin
- Memeriksa fundus uteri untuk memastikan kehamilan tunggal.
- Menyuntikan Oksitosin 10 IU secara intramuskuler pada bagian luar paha kanan 1/3
atas setelah melakukan aspirasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa ujung
jarum tidak mengenai pembuluh darah.
2. Peregangan Tali Pusat Terkendali
- Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva atau
menggulung tali pusat
- Meletakan tangan kiri di atas simpisis menahan bagian bawah uterus, sementara
tangan kanan memegang tali pusat menggunakan klem atau kain kasa dengan
jarak 5-10 cm dari vulva
- Saat uterus kontraksi, menegangkan tali pusat dengan tangan kanan sementara
tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorso-kranial
-
3. Mengeluarkan plasenta
- Jika dengan penegangan tali pusat terkendali tali pusat terlihat bertambah panjang
dan terasa adanya pelepasan plasenta, minta ibu untuk meneran sedikit sementara
tangan kanan menarik tali pusat ke arah bahwa kemudian ke atas sesuai dengan
kurve jalan lahir hingga plasenta tampak pada vulva.
- Bila tali pusat bertambah panjang tetapi plasenta belum lahir, pindahkan kembali
klem hingga berjarak 5-10 dari vulva.
- Bila plasenta belum lepas setelah mencoba langkah tersebut selama 15 menit
- Suntikan ulang 10 IU Oksitosin i.m
- Periksa kandung kemih, lakukan kateterisasi bila penuh
- Tunggu 15 menit, bila belum lahir lakukan tindakan plasenta manual
4. Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati. Bila
terasa ada tahanan, penegangan plasenta dan selaput secara perlahan dan sabar untuk
mencegah robeknya selaput ketuban.
5. Masase Uterus
- Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus uteri dengan
menggosok fundus secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri
hingga kontraksi uterus baik (fundus teraba keras)
6. Memeriksa kemungkinan adanya perdarahan pasca persalinan
- Kelengkapan plasenta dan ketuban
- Kontraksi uterus
- Perlukaan jalan lahir
-
Pengelolaan Atonia Uteri
- ajarkan keluarga melakukan Kompresi Bimanual Eksterna (KBE) - keluarkan tangan (KBI) secara hati-hati - suntikan Methyl ergometrin 0,2 mg i.m - pasang infus RL + 20 IU Oksitosin, guyur - lakukan lagi KBI
- Rujuk siapkan laparotomi - Lanjutkan pemberian infus + 20 IU Oksitosin minimal 500 cc/jam hingga mencapai tempat rujukan - Selama perjalanan dapat dilakukan kompresi aorta abdominalis atau kompresi bimanual eksternal
Masase fundus uteri Segera sesudah plasenta lahir
(maksimal 15 detik)
Uterus kontaksi ? Evaluasi rutin
- Evaluasi/ bersihkan bekuan darah/ selaput ketuban - Kompresi Bimanual Interna (KBI) maks. 5 menit
Uterus kontraksi ? - pertahankan KBI selama 1-2
menit - keluarkan tangan secara hati-
hati - lakukan pengawasan kala IV
Uterus kontraksi ? Pengawasan kala IV
Ligasi arteri uterina dan/ atau hipogastrika B-Lynch method
Perdarahan Pertahankan uterus
Histerektomi
berhenti
tetap
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
-
Tabel . Langkah-langkah rinci penatalaksanaan atonia uteri pascapersalinan No. Langkah Keterangan
1. Lakukan masase fundus uteri segera setelah plasenta dilahirkan
Masase merangsang kontraksi uterus. Sambil melakukan masase sekaligus dapat dilaku-kan penilaian kontraksi uterus
2. Bersihkan kavum uteri dari selaput ketuban dan gumpalan darah.
Selaput ketuban atau gumpalan darah dalam kavum uteri akan dapat menghalangi kontraksi uterus secara baik
3. Mulai lakukan kompresi bimanual interna. Jika uterus berkontraksi keluarkan tangan setelah 1-2 menit. Jika uterus tetap tidak berkontraksi teruskan kompresi bimanual interna hingga 5 menit
Sebagian besar atonia uteri akan teratasi dengan tindakan ini. Jika kompresi bimanual tidak berhasil setelah 5 menit, diperlukan tindakan lain
4. Minta keluarga untuk melakukan kompresi bimanual eksterna
Bila penolong hanya seorang diri, keluarga dapat meneruskan proses kompresi bimanual secara eksternal selama anda melakukan langkah-langkah selanjutnya.
5. Berikan Metil ergometrin 0,2 mg intramuskular/ intra vena
Metil ergometrin yang diberikan secara intramuskular akan mulai bekerja dalam 5-7 menit dan menyebabkan kontraksi uterus
Pemberian intravena bila sudah terpasang infus sebelumnya
6. Berikan infus cairan larutan Ringer laktat dan Oksitosin 20 IU/500 cc
Anda telah memberikan Oksitosin pada waktu penatalaksanaan aktif kala tiga dan Metil ergometrin intramuskuler. Oksitosin intravena akan bekerja segera untuk menyebabkan uterus berkontraksi.
Ringer Laktat akan membantu memulihkan volume cairan yang hilang selama atoni. Jika uterus wanita belum berkontraksi selama 6 langkah pertama, sangat mungkin bahwa ia mengalami perdarahan postpartum dan memerlukan penggantian darah yang hilang secara cepat.
7. Mulai lagi kompresi bimanual interna atau Pasang tampon uterovagina
Jika atoni tidak teratasi setelah 7 langkah pertama, mungkin ibu mengalami masalah serius lainnya.
Tampon uterovagina dapat dilakukan apabila penolong telah terlatih.
Rujuk segera ke rumah sakit 8. Buat persiapan untuk merujuk segera
Atoni bukan merupakan hal yang sederhana dan memerlukan perawatan gawat darurat di fasilitas dimana dapat dilaksanakan bedah dan pemberian tranfusi darah
9. Teruskan cairan intravena hingga ibu mencapai tempat rujukan
Berikan infus 500 cc cairan pertama dalam waktu 10 menit. Kemudian ibu memerlukan cairan tambahan, setidak-tidaknya 500 cc/jam pada jam pertama, dan 500 cc/4 jam pada jam-jam berikutnya. Jika anda tidak mempunyai cukup persediaan cairan intravena, berikan cairan 500 cc yang ketiga tersebut secara perlahan, hingga cukup untuk sampai di tempat rujukan. Berikan ibu minum untuk tambahan rehidrasi.
10. Lakukan laparotomi :
Pertimbangkan antara tindakan mempertahankan uterus dengan ligasi arteri uterina/ hipogastrika atau histerektomi.
Pertimbangan antara lain paritas, kondisi ibu, jumlah perdarahan.
-
Tabel : Jenis Uterotonika dan cara pemberiannya
JENIS DAN CARA OKSITOSIN ERGOMETRIN MISOPROSTOL
Dosis dan cara pemberian awal
IV: 40 unit dalam 1 L larutan garam fisiologis dengan tetesan cepat
IM: 10 unit
IM atau IV (lambat): 0,2 mg
Oral atau rektal 400-600 mg
Dosis lanjutan IV: 20 unit dalam 1 L larutan garam fisiologis dengan 40 tts/mnt
Ulangi 0,2 mg IM setelah 15 menit Bila masih diperlukan, beri IM/IV setiap 2-4 jam
400-600 mg 2-4 jam setelah dosis awal
Dosis maksimal per hari
Tidak lebih dari 3 L larutan dengan oksitosin 40 unit per botol
Total 1 g atau 5 dosis
Total 1200 mg atau 2-3 dosis ulangan
Indikasikontra atau hati-hati
Pemberian IV secara cepat atau bolus
Pre-eklampsia, vitium cordis, hipertensi
Nyeri kontraksi, asthma, menggigil, diare
Kompresi Bimanual Internal
Letakan satu tangan anda pada dinding perut, dan usahakan untuk menahan bagian
belakang uterus sejauh mungkin. Letakkan tangan yang lain pada korpus depan dari
dalam vagina, kemudian tekan kedua tangan untuk mengkompresi pembuluh darah
di dinding uterus. Amati jumlah darah yang keluar yang ditampung dalam pan. Jika
perdarahan berkurang, teruskan kompresi, pertahankan hingga uterus dapat
berkontraksi atau hingga pasien sampai di tempat rujukan. Jika tidak berhasil,
cobalah mengajarkan pada keluarga untuk melakukan kompresi bimanual eksternal
sambil penolong melakukan tahapan selanjutnya untuk penatalaksaan atonia uteri.
-
Gambar 4-1. Kompresi bimanual uteri internal Kompresi Bimanual Eksternal
Letakkan satu tangan anda pada dinding perut, dan usahakan sedapat mungkin
meraba bagian belakang uterus. Letakan tangan yang lain dalam keadaan terkepal
pada bagian depan korpus uteri, kemudian rapatkan kedua tangan untuk menekan
pembuluh darah di dinding uterus dengan jalan menjepit uterus di antara kedua
tangan tersebut (gambar 4.2).
Gambar 4-2. Kompresi bimanual eksternal
-
Robekan jalan lahir Perdarahan dalam keadaan di mana plasenta telah lahir lengkap dan kontraksi rahim
baik, dapat dipastikan bahwa perdarahan tersebut berasal dari perlukaan jalan lahir.
Perlukaan jalan terdiri dari:
a. Robekan Perineum
b. HematomaVulva
c. Robekan dinding vagina
d. Robekan serviks
e. Ruptura uteri
Robekan Perineum
Dibagi atas 4 tingkat
Tingkat I : robekan hanya pada selaput lendir vagina dengan atau tanpa
mengenai kulit perineum
Tingkat II : robekan mengenai selaput lendir vagina dan otot perinei
transversalis,
tetapi tidak mengenai sfingter ani
Tingkat III : robekan mengenai seluruh perineum dan otot sfingter ani
Tingkat IV : robekan sampai mukosa rektum
Kolporeksis adalah suatu keadaan di mana terjadi robekan di vagina bagian atas,
sehingga sebagian serviks uteri dan sebagian uterus terlepas dari vagina. Robekan
ini memanjang atau melingkar.
Robekan serviks dapat terjadi di satu tempat atau lebih. Pada kasus partus
presipitatus, persalinan sungsang, plasenta manual, terlebih lagi persalinan operatif
pervaginam harus dilakukan pemeriksaan dengan spekulum keadaan jalan lahir
termasuk serviks.
Pengelolaan
a. Episiotomi, robekan perineum, dan robekan vulva
Ketiga jenis perlukaan tersebut harus dijahit.
1. Robekan perineum tingkat I
-
Penjahitan robekan perineum tingkat I dapat dilakukan dengan memakai
catgut yang dijahitkan secara jelujur atau dengan cara jahitan angka delapan
(figure of eight).
2. Robekan perineum tingkat II
Sebelum dilakukan penjahitan pada robekan perineum tingkat I atau tingkat
II, jika dijumpai pinggir robekan yang tidak rata atau bergerigi, maka pinggir
yang bergerigi tersebut harus diratakan terlebih dahulu. Pinggir robekan
sebelah kiri dan kanan masing-masing dijepit dengan klem terlebih dahulu,
kemudian digunting. Setelah pinggir robekan rata, baru dilakukan penjahitan
luka robekan.
Mula-mula otot-otot dijahit dengan catgut, kemudian selaput lendir vagina
dijahit dengan catgut secara terputus-putus atau delujur. Penjahitan mukosa
vagina dimulai dari puncak robekan. Sampai kulit perineum dijahit dengan
benang catgut secara jelujur.
3. Robekan perineum tingkat III
Pada robekan tingkat III mula-mula dinding depan rektum yang robek dijahit,
kemudian fasia perirektal dan fasial septum rektovaginal dijahit dengan catgut
kromik, sehingga bertemu kembali. Ujung-ujung otot sfingter ani yang
terpisah akibat robekan dijepit dengan klem / pean lurus, kemudian dijahit
dengan 2 3 jahitan catgut kromik sehingga bertemu lagi. Selanjutnya
robekan dijahit lapis demi lapis seperti menjahit robekan perineum tingkat II.
4. Robekan perineum tingkat IV
Pada robekan perineum tingkat IV karena tingkat kesulitan untuk melakukan
perbaikan cukup tinggi dan resiko terjadinya gangguan berupa gejala sisa
dapat menimbulkan keluhan sepanjang kehidupannya, maka dianjurkan
apabila memungkinkan untuk melakukan rujukan dengan rencana tindakan
perbaikan di rumah sakit kabupaten/kota.
b. Hematoma vulva
1. Penanganan hematoma tergantung pada lokasi dan besar hematoma. Pada
hematoma yang kecil, tidak perlu tindakan operatif, cukup dilakukan kompres.
-
2. Pada hematoma yang besar lebih-lebih disertai dengan anemia dan presyok,
perlu segera dilakukan pengosongan hematoma tersebut. Dilakukan sayatan
di sepanjang bagian hematoma yang paling terenggang. Seluruh bekuan
dikeluarkan sampai kantong hematoma kosong. Dicari sumber perdarahan,
perdarahan dihentikan dengan mengikat atau menjahit sumber perdarahan
tersebut. Luka sayatan kemudian dijahit. Dalam perdarahan difus dapat
dipasang drain atau dimasukkan kasa steril sampai padat dan meninggalkan
ujung kasa tersebut diluar.
c. Robekan dinding vagina
1. Robekan dinding vagina harus dijahit.
2. Kasus kolporeksis dan fistula visikovaginal harus dirujuk ke rumah sakit.
d. Robekan serviks
Robekan serviks paling sering terjadi pada jam 3 dan 9. Bibir depan dan
bibir belakang serviks dijepit dengan klem Fenster (Gambar 4.3).
Kemudian serviks ditarik sedikit untuk menentukan letak robekan dan
ujung robekan. Selanjutnya robekan dijahit dengan catgut kromik dimulai
dari ujung robekan untuk menghentikan perdarahan.
-
A. Jahitan pertama dimulai dari puncak
robekan pada serviks B. Sebagian robekan serviks setelah
dijahit
Gambar 4-3. Teknik menjahit robekan serviks
Retensio Plasenta Retensio plasenta ialah plasenta yang belum lahir dalam setengah jam
setelah janin lahir. Plasenta yang belum lahir dan masih melekat di dinding
rahim oleh karena kontraksi rahim kurang kuat untuk melepaskan plasenta
disebut plasenta adhesiva. Plasenta yang belum lahir dan masih melekat di dinding rahim oleh karena villi korialisnya menembus desidua sampai
miometrium disebut plasenta akreta. Plasenta yang sudah lepas dari dinding rahim tetapi belum lahir karena terhalang oleh lingkaran konstriksi di bagian
bawah rahim disebut plasenta inkarserata. Perdarahan hanya terjadi pada plasenta yang sebagian atau seluruhnya telah lepas dari dinding rahim.
Banyak atau sedikitnya perdarahan tergantung luasnya bagian plasenta yang
telah lepas dan dapat timbul perdarahan. Melalui periksa dalam atau tarikan
pada tali pusat dapat diketahui apakah plasenta sudah lepas atau belum dan
bila lebih dari 30 menit maka kita dapat melakukan plasenta manual.
Prosedur plasenta manual sebagai berikut:
-
Sebaiknya pelepasan plasenta secara manual dilakukan dalam narkosis, karena relaksasi otot memudahkan pelaksanaannya terutama bila retensi telah lama. Sebaiknya juga dipasang infus NaCl 0,9% sebelum tindakan dilakukan. Setelah desinfektan tangan dan vulva termasuk daerah seputarnya, labia dibeberkan dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan dimasukkan secara obstetrik ke dalam vagina.
Sekarang tangan kiri menahan fundus untuk mencegah kolporeksis. Tangan kanan dengan posisi obstetrik menuju ke ostium uteri dan terus ke lokasi plasenta; tangan dalam ini menyusuri tali pusat agar tidak terjadi salah jalan (false route).
Supaya tali pusat mudah diraba, dapat diregangkan oleh pembantu (asisten). Setelah tangan dalam sampai ke plasenta, maka tangan tersebut dipindahkan ke pinggir plasenta dan mencari bagian plasenta yang sudah lepas untuk menentukan bidang pelepasan yang tepat. Kemudian dengan sisi tangan kanan sebelah kelingking (ulner), plasenta dilepaskan pada bidang antara bagian plasenta yang sudah terlepas dan dinding rahim dengan gerakan yang sejajar dengan dinding rahim. Setelah seluruh plasenta terlepas, plasenta dipegang dan dengan perlahan-lahan ditarik keluar.
Kesulitan yang mungkin dijumpai pada waktu pelepasan plasenta secara manual ialah adanya lingkaran konstriksi yang hanya dapat dilalui dengan dilatasi oleh tangan dalam secara perlahan-lahan dan dalam nakrosis yang dalam. Lokasi plasenta pada dinding depan rahim juga sedikit lebih sukar dilepaskan daripada lokasi di dinding belakang. Ada kalanya plasenta tidak dapat dilepaskan secara manual seperti halnya pada plasenta akreta, dalam hal ini tindakan dihentikan.
Setelah plasenta dilahirkan dan diperiksa bahwa plasenta lengkap, segera
dilakukan kompresi bimanual uterus dan disuntikkan Ergometrin 0.2 mg IM atau IV sampai kontraksi uterus baik. Pada kasus retensio plasenta, risiko
atonia uteri tinggi oleh karena itu harus segera dilakukan tindakan
pencegahan perdarahan postpartum.
Apabila kontraksi rahim tetap buruk, dilanjutkan dengan tindakan sesuai
prosedur tindakan pada atonia uteri.
Plasenta akreta ditangani dengan histerektomi oleh karena itu harus dirujuk ke rumah sakit.
-
Gambar 4-5. Pelepasan plasenta secara manual
Sisa Plasenta Sisa plasenta dan ketuban yang masih tertinggal dalam rongga rahim dapat
menimbulkan perdarahan postpartum dini atau perdarahan pospartum lambat
(biasanya terjadi dalam 6 10 hari pasca persalinan). Pada perdarahan
postpartum dini akibat sisa plasenta ditandai dengan perdarahan dari rongga
rahim setelah plasenta lahir dan kontraksi rahim baik. Pada perdarahan
postpartum lambat gejalanya sama dengan subinvolusi rahim, yaitu
perdarahan yang berulang atau berlangsung terus dan berasal dari rongga
rahim. Perdarahan akibat sisa plasenta jarang menimbulkan syok.
Penilaian klinis sulit untuk memastikan adanya sisa plasenta, kecuali apabila
penolong persalinan memeriksa kelengkapan plasenta setelah plasenta lahir.
Apabila kelahiran plasenta dilakukan oleh orang lain atau terdapat keraguan
akan sisa plasenta, maka untuk memastikan adanya sisa plasenta ditentukan
dengan eksplorasi dengan tangan, kuret atau alat bantu diagnostik yaitu
ultrasonografi. Pada umumnya perdarahan dari rongga rahim setelah
plasenta lahir dan kontraksi rahim baik dianggap sebagai akibat sisa plasenta
yang tertinggal dalam rongga rahim.
-
Pengelolaan
1. Pada umumnya pengeluaran sisa plasenta dilakukan dengan kuretase.
Dalam kondisi tertentu apabila memungkinkan, sisa plasenta dapat
dikeluarkan secara manual. Kuretase harus dilakukan di rumah sakit dengan hati-hati karena dinding
rahim relatif tipis dibandingkan dengan kuretase pada abortus.
2. Setelah selesai tindakan pengeluaran sisa plasenta, dilanjutkan dengan
pemberian obat uterotonika melalui suntikan atau per oral.
3. Antibiotika dalam dosis pencegahan sebaiknya diberikan.
Inversi uterus (traction)
Inversi uterus jarang terjadi, dengan insiden 0,05 % dari persalinan.
Manajemen aktif kala III dapat mengurangi kejadian ini. Implantasi
plasenta pada fundus, penekanan pada fundus dan tarikan tali pusat
yang kuat dapat menyebabkan inversi uteri. Inversi uteri tampak
sebagai masa abu-abu kebiruan yang keluar dari vagina. Efek
vasovagal menyebabkan perubahan tanda vital yang tidak sesuai
dengan jumlah perdarahan. Plasenta sering masih lengket dan tetap
biarkan pada insersinya sampai proses reposisi selesai.(Cunningham,
2005; Anderson, 2007).
-
Gambar 6. Metode reposisi Johnson (Anderson, 2007)
Reposisi metode Johnson dimulai dengan menggenggam fundus yang
keluar dengan telapak tangan dan jari kearah forniks posterior. Uterus
dikembalikan ke posisi semula dengan sedikit pengangkatan keatas
melalui pelvis ke dalam abdomen. Setelah uterus kembali, obat
uterotonika harus diberikan untuk merangsang kontraksi uterus dan
mencegah inversi terulang kembali. Jika tindakan awal ini gagal atau
terjadi lingkaran kontraksi pada serviks, pemberian magnesium sulfat,
terbutalin, nitroglycerin atau anestesi umum dapat diberikan untuk
relaksasi uterus sehingga proses reposisi dapat dilanjutkan. Jika
metode ini masih gagal harus dilakukan pembedahan. (Anderson,
2007; Yiadom, 2010).
Tampon intra uterin Tampon intra uterin memberikan tekanan pada dinding uterus untuk
menghentikan perdarahan. Tindakan ini dapat dilakukan dengan 2 cara :
1. Insersi tampon uteri yang berisi kasa gulung yang dimasukkan ke
dalam uterus dengan padat sebagai tekanan langsung terhadap
-
pembuluh darah vena, kapiler atau perembesan dari desidua
sehingga perdarahan berkurang atau berhenti. Tampon ini sebelum
dipasang harus diberi krim antibiotika dan harus dikeluarkan dalam
waktu 24 48 jam. (Danso, 2006; Godhake, 2008; Smith, 2010)
Teknik ini dikembangkan sejak tahun 1950, tetapi saat ini sudah tidak
dipakai lagi karena mempunyai kerugian sebagai berikut : (Danso, 2006)
- Dibutuhkan ketrampilan untuk memasukkan tampon dengan
padat dan cepat.
- Keterlambatan dalam mengenali perdarahan yang berlanjut
karena darah meresap ke dalam kasa terlebih dahulu sebelum
tampak keluar dari vagina.
- Keberhasilan prosedur ini tidak bisa dinilai dengan cepat.
- Kesulitan dalam menentukan kepadatan kasa.
- Resiko terjadi trauma dan infeksi
- Pengeluaran tampon kadang memerlukan tindakan operatif untuk
dilatasi serviks dan ekstraksi kasa.
2. Insersi balon yang dikembangkan dalam kavum uteri dan mengisi
seluruh ruang sehingga memberikan tekanan intra uteri yang lebih
besar dari tekanan arteri.
Pemakaian balon pertama kali dilakukan oleh Condous tahun 2003
untuk menentukan indeks prognostik apakah laparotomi diperlukan
pada penderita dengan perdarahan pasca salin masif yang tidak
respon terhadap terapi medik. Kateter esophagus Sengstaken-
Blakemore dimasukkan ke dalam kavum uteri melalui serviks dengan
panduan USG dan diisi dengan cairan saline hangat sampai balon
yang mengembang teraba pada abdomen dan terlihat pada bagian
terendah kanal serviks. Jenis balon lain yang dipakai adalah balon
urologi hidostatik Rusch, balon Bakri, kateter Foley dan kondom -
kateter. (Danso, 2006; Godhake, 2008).
-
Sengstaken-Balkemore tube Rusch hydrostatic ballon catheter Bakri ballon
Sayeba Kondom - kateter Gambar . Jenis tampon balon untuk perdarahan pasca salin (Lynch, 2006 dan Sayeba, 2003)
Penemuan inovatif di Bangladesh menggunakan kondom sebagai tampon
balon dikenal sebagai metode Sayeba. Kateter steril dimasukkan ke dalam
kondom dan diikat dekat pada pangkal kondom dengan benang steril,
-
bagian luar kateter dihubungkan dengan infus cairan saline. Kondom
kateter kemudian dimasukkan ke dalam uterus dan dikembangkan dengan
cairan saline 250 500 ml. Bagian luar kateter kemudian ditekuk atau
diikat jika perdarahan berkurang atau berhenti. Kontraksi uterus
dipertahankan dengan uterotonika minimal 6 jam dan tampon
dipertahankan selama 24 48 jam. Pada penelitian 23 kasus perdarahan
pasca salin karena atonia uteri di Bangladesh, perdarahan berhenti dalam
waktu 15 menit pada semua kasus. (Danso, 2006).
Di RS Dr. Soetomo, metode ini sudah diterapkan sejak tahun 2005, pada
penelitian 12 kasus perdarahan pasca salin karena atonia uteri,
keberhasilan mencapai 100 %. (Sulistyono, 2006).
-
Daftar Pustaka
Danso D, Reginald PW, 2006. Internal uterine tamponade. A textbook of
postpartum hemorrhage. UK : Sapiens, 28 : 263 267, 1st Ed
Danso D, Reginald PW, 2006. Internal uterine tamponade. A textbook of
postpartum hemorrhage. UK : Sapiens, 28 : 263 267, 1st Ed
Ghodake VB, Pandit SN, 2008. Role of modified B-Lynch suture in modern day
management of atonic postpartum haemorrhage. Bombay hospital
journal, 50(2) : 205 211
Miller S, Lester F, 2004. Prevention and treatment of postpartum hemorrhage :
new advances for low-resource settings. Journal of midwifery and
womens health, 49 : 283 292
Saifudin A, 2005. Upaya Safe Motherhood dan Making Pregnancy Safer,
Bungai Rampai Obstetri dan Ginekologi Sosial, Yayasan Bina Pustaka
Sarwono Prawirohardjo,. 221
Sulistyono A, Dachlan EG, 2006. Pengalaman menggunakan tampon kondom
(metode Sayeba) pada hemoragia pasca persalinan (HPP). Majalah
Obstetri dan Ginekologi Indonesia, 15(3) : 98 - 102
WHO, UNICEF, UNFPA and the World Bank. Geneva. 2007. Maternal mortality
in 2005: estimates developed by WHO, UNICEF, UNFPA and world
bank, 1
World Health Organization (WHO), 2005. What is the effectiveness of antenatal
care?, Supplement,
World Health Organization (WHO), 2006. Mortality Country Fact Sheet
2006/Indonesia. 2006.
http://www.who.int/whosis/mort/profiles/mort_searo_idn_indonesia
.pdf
World Health Organization (WHO). 200. Country Health System Profile-Indonesia / MDGs
Yasmin S, 2003. B-lynch brace suture as an alternative to hysterectomy for
severe PPH. Pakistan journal medical, 42(3)
-
Yiadom MY, Carusi D, 2010. Pregnancy, postpartum hemorrhage. http://www.emedicine.medscape.com/article/796785