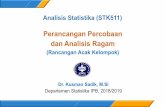Percobaan VI Kognosi Kadar Air
-
Upload
mario-moore -
Category
Documents
-
view
232 -
download
12
description
Transcript of Percobaan VI Kognosi Kadar Air
PERCOBAAN VIPENETAPAN KADAR AIR DENGAN METODE AZEOTROPH
A. Tujuan
Mengenal dan memahami prinsip penentapan kadar air dengan metode azeotroph.
B. Dasar Teori
1. Penetapan Kadar Air
Air merupakan komponen yang paling penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan tidak terkecuali bahan pangan dan makanan. Semua bahan makanan mengandung air dalam jumlah yang berbeda-beda. Air dalam makanan dapat mempengaruhi penampakan, tekstur serta cita rasa makanan itu sendiri. Air juga terdapat dalam bahan makanan yang kering dan secara kasat mata tidak terlihat seperti tepung-tepungan dan biji-bijian dalam jumlah tertentu.Kandungan air dalam bahan makanan ikut menentukan acceptability. Sebagian besar perubahan dalam bahan makanan terjadi dalam media air yang ditambahkan atau yang berasal dari makanan itu sendiri. Adanya senyawa ataupun kandungan air akan mempengaruhi keseluruhan mutu makanan secara kimia dan mikrobiologi.
(Winarto, 2004)Air dalam bahan makanan dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut:
a. Air bebas
Adalah air yang terdapat dalam ruang-ruang antar sel dan intra gramular serta pori-pori yang terdapat dalam suatu bahan.
b. Air terikat secara lemah
Hal ini terjadi karena air tersebut terserap atau terabsorbsi pada suatu permukaan koloid makromolekuler seperti pektin, protein, pati, selulosa. Selain itu juga terabsorbsi diantara koloid tersebut dan merupakan suatu pelarut zat-zat yang ada didalam sel.
c. Air dalam keadaan terikat kuat
Yaitu membentuk hidrat, dimana ikatan bersifat kuat sehingga akan sukar untuk diuapkan. Dan air ini tidak akan membeku meskipun pada suhu 0 F.(Sudarmadji, 2010)Penentuan atau penetapan kandungan air dapat dilakukan dalam beberapa cara. Hal ini tergantung pada sifat bahannya. Pada umumnya penentuan kadar air dilakukan dengan menggeringkan bahan-bahan dalam oven pada suhu 105-110 C selama tiga jam atau hingga diperoleh berat yang konstan. Untuk bahan yang tidak tahan panas, seperti bahan yang memiliki kadar gula tinggi, minyak, daging, kecap, dan lain-lain. Biasanya pemanasan dilakukan menggunakan oven vakum dengan suhu yang lebih rendah. Kadang-kadang pengeringan dilakukan tanpa pemanasan. Bahan dimasukkan ke dalam desikator dengan H2SO4 pekat sebagai pengering, hingga mencapai berat yang konstan.
Penentuan kadar air dari bahan-bahan yang kadar airnya tinggi dan mengandung senyawa-senyawa yang mudah menguap seperti sayuran dan susu, menggunakan metode destilasi dengan pelarut tertentu. Selain itu, untuk bahan-bahan yang mengandung kadar air yang tinggi, kadar airnya dapat diukur dengan menggunakan refraktometer disamping menentukan padatan terlarutnya pula. Disamping cara fisik adapula cara kimia untuk menentukan kadar air berdasarkan volume gas etilen yang dihasilkan dari reaksi kalium dalam bahan yang akan diperiksa. Cara ini dipergunakan untuk bahan-bahan seperti sabun, tepung, kulit, bubuk biji vedilli, mentega dan sari buah.(Winarto, 2004)Penentuan kadar air dalam bahan pangan dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode pengeringan (dengan oven biasa), metode destilasi, metode kimia, dan metode khusus (kromatografi dan Nuclear Magnetic Resonance). Kadar air dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:Kadar air = x 100%
Keterangan :
A : cawan + berat kosong (g)
B : cawan kosong (g)
C : bobot sampel (g)
(Santi, 2012)2. Metode Destilasi AzeotrophMetode destilasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk menentukan kadar air suatu bahan yang mudah menguap, memiliki kandungan air yang tinggi dan bahan-bahan yang mudah teroksidasi. Metode ini digunakan untuk bahan-bahan yang memiliki ciri-ciri tersebut, agar pengeringan yang dilakukan tidak menghilangkan kadar air seluruhnya. Destilasi dilakukan dalam tiga tahap yaitu evaporasi, yakni memindahkan suatu pelarut sebagai uap dari cairan. Pemisahan uap dilakukan didalam klum. Hal ini bertujuan untuk mempermudah komponen dengan titik didih lebih rendah yang lebih voktil dari komponen lain yang kurang voktil, dan kondensasi dari uap cairan untuk mendapatkan fraksi pelarut yang lebih voktil. Metode destilasi ini biasa menggunakan suatu pelarut yang immiserible, yaitu suatu pelarut yang tidak saling bercampur dengan air dan disuling bersama-sama dengan sampel yang telah ditimbang dengan teliti. Pelarut tersebut memiliki titik didih yang sedikit lebih diatas titik didih air. Pelarut yang biasa digunakan adalah toluen dan campuran dari pelarut-pelarut lain. Metode ini sering digunakan pada produk-produk atau bahan pangan yang mengandung sedikit air atau mengandung senyawa voktil, diantaranya adalah kayu biru, keju, dan bahan voktil seperti rempah-rempah yang banyak mengandung voktil.
(Guenther, 1987)Destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan-bahan kimia berdasarkan perbedaan kecapan atau kemudahan menguap (volatilitas) dari suatu bahan atau dapat didefenisikan juga sebagai suatu teknik pemisahan kimia yang berdasarkan atas perbedaan titik didih. Dalam penyulingan campuran dari zat tersebut dididihkan sampai menguap, dan uap ini kemudian didinginkan kembali dalam bentuk cairan. Zat-zat yang memiliki titik didih yang lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Metode ini merupakan metode yang termasuk dalam unit operasi kimia jenis perpindahan massa. Penerapan proses ini didasarkan pada teori bahwa pada suatu larutan, masing-masing komponen akan menguap pada titik didihnya. Model ideal dari destilasi didasarkan pada hukum Dalton (Winarto, 2004).Dua tahap utama yang terjadi dalam proses destilasi yaitu pendidihan dan pengembunan. Pendidihan terjadi dengan cara pemanasan (penguapan) dan pengembunan kembali. Selain untuk memisahkan dan memurnikan, destilasi juga dapat digunakan untuk identifikasi suatu senyawa organik cair yang belum diketahui. Titik didih suatu zat cair dipengaruhi oleh interaksi antar gaya Van Der Walls, interaksi dipol-dipol, dan juga ikatan hidrogen.
Destilasi azeotroph pada prinsipnya digunakan untuk memastikan suatu campuran azeotroph, yairu campuran dua atau lebih komponen yang sulit dipisahkan. Pada umumnya dalam proses destilasi azeotroph ini menggunakan senyawa lain untuk memisahkan ikatan azeotroph. Azeotroph merupakan campuran dua atau lebih komponen pada komposisi tertentu dimana komposisi tersebut tidak dapat berubah hanya melalui destilasi biasa. Ketika campuran azeotroph dididihkan, pada uap yang dihasilkan memiliki komposisi yang sama dengan fasa cairnya. Dengan kata lain campuran yang komposisinya senantiasa tetap meskipun cairan tersebut dididihkan.(Svehla, 1979)3. Simplisia
Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat, belum mengalami proses pengolahan apapun dan jika tidak dinyatakan lain. Simplisia merupakan bahan yang dikeringkan. Simplisia dapat berupa simplisia nabati, simplisia hewani, dan simplisia pelikan atau mineral.
Untuk menjamin keseragaman senyawa aktif, kemurnian dan kegunaannya, simplisia harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:a. Bahan baku simplisia
b. Proses pembuatan simplisia
c. Cara pengepakan dan penyimpanan simplisia
(Suharmiati, 2012)Persyaratan simplisia hewani dan nabati yaitu:
a. Tidak boleh mengandung mikroorganisme pathogen
b. Harus bebas campuran mikroorganisme, serangga, dan binatang lain
c. Tidak boleh ada penyimpangan bau dan warna
d. Tidak boleh mengandung lendir atau menunjukkan adanya kerusakan
(Syamsuri, 2006)4. Uraian Tanamana. Mahkota Dewa
Sistematika tumbuhan mahkota dewa adalah sebagai berikut:
Kingdom: Plantae
Divisi: Spermatophyta
Kelas: Thynolaceales
Famili: Thynoleaceae
Marga: Phaleria
Species: Phaleria macrocarpa
Mahkota dewa merupakan tanaman asli Indonesia yang dapat digunakan sebagai obat tradisional untuk mengobati asam urat, diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit ginjal. Selain berperan dalam penyakit metabolik, tanaman ini juga bersifat sitotoksik dan mampu menghambat poliferasi sel kanker payudara. Meskipun khasiat mahkota dewa telah diungkap, belum ada penelitian yang mengkaji tentang mekanisme mahkota dewa sebagai antioksidan.
(Bambang, 2009)Dapat berkhasiat untuk melancarkan peredaran darah, menurunkan kolesterol, mengobati alergi dan juga membantu membuang racun dari dalam tubuh. Mahkota dewa mengandung senyawa kimia antara lain alkaloid, saponin, flavonoid, fenol, dan minyak atsiri (Firman, 2009).b. Mengkudu
Sistematika tumbuhan mengkudu adalah sebagai berikut:
Kingdom: Plantae
Divisi: Spermatophyta
Kelas: Dicotyledonae
Famili: Rubiaceae
Marga: Morinda
Species: Morinda citrifolia
Termasuk dalam jenis tanaman pohon, berbatang bengkak, daunnya tunggal dengan ujung dan pangkal yang runcing. Buahnya termasuk buah yang berbongkol-bongkol tidak teratur, berdaging. Buah masak berwarna kuning kotor atau kekuning-kuningan.
(Djauhariya, 2003)Merupakan tanaman tropis dan liar, mengkudu dapat tumbuh ditepi pantai hingga ketinggian 1500 dpl. Ukuran dan bentuk buahnya bervariasi, pada umumnya mengandung banyak biji. Dalam satu buah terdapat 200 biji. Bijinya dibungkus oleh suatu lapisan atau kantong biji.Mengkudu digunakan sebagai obat batuk, radang amandel, tekanan darah tinggi, radang ginjal, radang empedu, dan radang usus, sakit pinggang dan dapat juga digunakan untuk pengobatan tumor dan kanker. Mengandung sejumlah antioksidan yang terdiri dari asam askorbat, flavonoid, asam linolenat, dan beta karoten. Kadar air buah mengkudu cukup tinggi yaitu 80-85 %. Kadar abu tidak boleh lebih dari 12 %. Kadar sari larut air tidak boleh kurang dari 3,6 % dan kadar sari larut etanol 2,5 %.
(Suprapti, 2000)5. Uraian Bahana. Toluen
Toluena adalah bahan kimia dengan aroma yang kuat dan khas. Senyawa ini ditemukan di alam pada jenis pohon balsam yang disebut balsam tolu, serta minyak mentah. Toluena dapat pula ditemukan sebagai aditif dalam berbagai produk seperti cat kuku, rokok, bensin, pewarna, parfum, bahan peledak, cat dan thinner, perekat, serta barang-barang manufaktur lainnya. Bahan kimia ini dapat mempengaruhi kesehatan seseorang bila dihirup atau ketika air yang terkontaminasi dengan toluena tertelan. Meskipun memiliki berbagai bahaya, toluena masih belum digolongkan sebagai senyawa karsinogen.
Gambar. Struktur Toluena(Oxtoby, 2001)C. Alat dan Bahan
1. Alat
a. Cawan porselen
b. Corong pisah
c. Gelas kimia 100 mL ; 500 mL
d. Gelas ukur 10 mL
e. Gunting
f. Klem dan Statif
g. Kondensor
h. Labu alas bulat
i. Pipet ukur 5 mL; 10 mL
j. Pro pipet
k. Sendok tanduk
l. Tabung penampung
m. Timbangan analitik
2. Bahan
a. Alumunium foil
b. Aquadest
c. Batu didih
d. Sampel simplisia buah mengkudu (Morinda citrifolia fructus)
e. Sampel simplisia daun mahkota dewa (Phaleria macrocarpa folium)
f. Sampel simplisia kulit buah jeruk keprok (Citrus nobilis fructus)
g. Toluen
D. Prosedur Kerja
1. Penjenuhan Toluen
a. Dimasukkan 2 mL aquadest dan 200-300 mL toluen ke dalam corong pisah
b. Dikocok corong pisah dengan kuat
c. Didiamkan hingga toluen dan aquades terpisah
d. Diambil bagian toluen
2. Penetapan Kadar Air
a. Dihaluskan 25 gram simplisia
b. Dimasukkan ke dalam labu alas bulat
c. Ditambahkan toluen yang telah dijenuhkan
d. Dipasang alat destilasi
e. Dilakukan destilasi
f. Ditampung campuran air-toluen ke dalam corong pisah
g. Didiamkan hingga terpisah antara air dan toluen
h. Diambil bagian airnya
i. Diukur volume kadar air simplisia
E. Hasil Pengamatan
1. Buah Mengkudu
Nama latin simplisia: Morinda citrifolia fructusNama latin tumbuhan: Morinda citrifoliaNama lain tumbuhan: Pace
a. Tabel Pengamatan
Volume Air (mL)Berat Simplisia (gram)% kadar air
0,2525,0110,99 %
b. Perhitungan
= 0,99 %
2. Buah Jeruk KeprokNama latin simplisia: Citrus reticulata fructusNama latin tumbuhan: Citrus reticulataNama lain tumbuhan: Limau
a. Tabel Pengamatan
Volume Air (mL)Berat Simplisia (gram)% kadar air
125,01973,99 %
b. Perhitungan
= 3,99 %
3. Daun Mahkota DewaNama latin simplisia: Phaleria macrocarpa foliumNama latin tumbuhan: Phaleria macrocarpaNama lain tumbuhan: Mahkota Raja
a. Tabel Pengamatan
Volume Air (mL)Berat Simplisia (gram)% kadar air
2,425,0259,59 %
b. Perhitungan
= 9,59 %
4. Gambar
a. Sampel
b. Alat destilasi
c. Hasil destilat
d. Pengukuran
F. Pembahasan
Percobaan ini mengenai penetapan kadar air dengan metode azeotroph dengan tujuan mengenal dan memahami prinsip penetapan kadar air dengan metode azeotroph. Adapun sampel yang digunakan yaitu simplisia daun mahkota dewa (Phaleria macrocarpa folium), buah mengkudu (Morinda citrifolia fructus) dan kulit buah jeruk keprok (Citrus nobilis fructus). Simplisia digunakan sebagai sampel pada percobaan ini dikarenakan untuk melihat kandungan air pada simplisia terkait dengan kualitas simplisia dan juga menilai proses pengeringan pada pembuatan simplisia apakah sudah memenuhi syarat atau tidak.
Pada umumnya bahan simplisia yang sudah kering memiliki kadar air 8-10 %. Kelebihan jumlah air dari rentang tersebut dalam simplisia tanaman akan mempercepat pertumbuhan mikroba, jamur, atau serangga dan pembusukan yang pada akhirnya diikuti oleh reaksi hidrolisis. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembatasan kadar air untuk setiap simplisia tanaman obat. Hal ini sangat penting, khususnya untuk simplisia tanaman obat yang dapat menyerap kelembaban dengan cepat atau dapat cepat membusuk dengan adanya air. Jika dapat dihasilkan simplisia terstandar, maka simplisia yang diperoleh tidak mudah rusak dan tahan disimpan dalam waktu lama.
Kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang dinyatakan dalam persen. Kadar air juga merupakan karakteristik yang sangat penting dalam bahan pangan karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, dan ikut menentukan kesegaran dan daya awet bahan tersebut. Tujuan dari penetapan kadar air adalah mengetahui batasan maksimal atau rentang besarnya kandungan air dalam suatu bahan. Hal ini terkait dengan kemurnian bahan dan adanya kontaminan dalam simplisia tersebut karena kandungan air yang tinggi dapat menyebabkan mudahnya bakteri, kapang, dan khamir untuk berkembang biak sehingga akan terjadi perubahan pada bahan pangan. Dengan demikian, penghilangan kadar air hingga jumlah tertentu berguna untuk memperpanjang daya tahan bahan selama penyimpanan.
Penetapan kadar air dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan metode titrimetri, azeotroph, dan metode gravimetri. Metode titrimetri didasarkan atas reaksi secara kuantitatif air dengan larutan anhidrat belerang dioksida dan iodium dengan adanya dapar yang bereaksi dengan ion hidrogen. Kelemahan dari metode ini adalah stoikiometri reaksi tidak tepat dan reproduksibilitas bergantung pada beberapa faktor seperti kadar relatif komponen pereaksi, sifat pelarut inert yang digunakan untuk melarutkan zat dan teknik yang digunakan pada penetapan tertentu. Metode ini juga memerlukan pengamatan titik akhir titrasi yang bersifat relatif dan diperlukan sistem dari kelembaban udara. Metode azotroph merupakan metode yang didasarkan pada perbedaan titik didih dari dua bahan yang sulit untuk dipisahkan. Metode ini efektif untuk penetapan kadar air karena terjadi penyulingan berulang kali di dalam labu alas bulat dan menggunakan pendingin balik untuk mencegah adanya penguapan berlebih. Sistem yang digunakan tertutup sehingga tidak dipengaruhi kelembaban. Sedangan metode gravimetri yaitu penetapan kadar air dengan menghitung susut pengeringan hingga bobot konstan tercapai. Kekurangan dari metode ini adalah membutuhkan waktu yang lama.
Sampel simplisia yang digunakan adalah daun mahkota dewa (Phaleria macrocarpa folium), buah mengkudu (Morinda citrifolia fructus) dan kulit buah jeruk keprok (Citrus nobilis fructus). Mahkota dewa tergolong tanaman perdu yang tumbuh di dataran rendah dan banyak digunakan sebagai bahan obat untuk menyembuhkan kanker dan diabetes mellitus. Daun mahkota dewa terkandung alkaloid, saponin dan polifenol. Saponin yang terkandung berupa saponin triterpenoid dan steroid. Kedua senyawa tersebut mempunyai efek antiinflamasi, analgetik, dan sitotoksik. Mengkudu termasuk tanaman pohon, buahnya mengandung minyak atsiri, alkaloid, saponin dan flavonoid. Sedangkan jeruk keprok merupakan tanaman pohon atau perdu dan jarang sekali berbentuk semak. Dinding buahnya mempunyai lapisan kulit luar yang tipis, kaku, menjangat dan mengandung banyak minyak atsiri, alkaloid, saponin, kumarin, dan flavonoid.
Percobaan dilakukan dalam dua tahap utama yaitu pembuatan simplisia dan penetapan kadar air. Tahap pertama yaitu pembuatan simplisia. Simplisia adalah bahan alamiah yang belum mengalami pengolahan apapun, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Prosedur pertama pembuatan simplisia yaitu pengumpulan bahan berupa bagian tanaman atau tanaman utuh. Kedua dilakukan sortasi basah untuk memisahkan bahan simplisia dari kotoran-kotoran atau bahan asing lainnya seperti tanah, kerikil, rumput, dan bagian tanaman serta pengotor yang perlu dibuang. Ketiga dilakukan pencucian untuk menghilangkan tanah dan kotoran yang melekat pada bahan simplisia. Pencucian dilakukan dengan air bersih, yang sebaiknya mengalir. Keempat dilakukan perajangan yaitu memotong bahan simplisia menjadi ukuran yang lebih kecil. Perajangan dilakukan untuk memperluas permukaan bahan sehingga mempermudah proses pengeringan dan pengepakan. Kelima, dilakukan pengeringan dengan menghilangkan kadar air sehingga simplisia tidak mudah ditumbuhi bakteri ataupun kapang yang dapat mengakibatkan terjadinya reaksi enzimatik dan kemudian mempengaruhi senyawa yang terkandung dalam simplisia, tujuan utama dari pengeringan adalah untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak sehingga dapat disimpan dalam waktu lama. Keenam, disortasi kering untuk memisahkan benda-benda asing atau pengotor lainnya yang masih tertinggal pada simplisia kering. Ketujuh, simplisia kering dikemas (pengepakan) pada wadah yang sesuai dan tidak bereaksi dengan simplisia. Tahap terakhir dari pembuatan simplisia yaitu penyimpanan, umumnya pada suhu kamar.
Tahap kedua yaitu penetapan kadar air denga metode azeotroph. Azeotroph adalah campuran dua atau lebih zat yang memiliki titik didih minimal dan maksimal dimana komposisi tidak dapat diubah dengan cara destilasi sederhana. Prinsip dari penetapan kadar air secara destilasi azeotroph ini yaitu simplisia didihkan dengan pelarut yang dapat menarik air namun tidak bercampur dengan air seperti toluen dan xylene, sehingga air dalam simplisia akan dibawa oleh pelarut tersebut saat mencapai titik didih pelarut dalam bentuk uap, kemudian dikondensasi dan uap berubah menjadi tetesan yang akan ditampung oleh penampung. Tetesan ini mengandung pelarut dan air yang akan memisah setelah didiamkan. Pemisahan senyawa dengan destilasi bergantung pada perbedaan tekanan uap senyawa dalam campuran. Jika suhu dinaikkan, tekanan uap cairan akan naik sampai tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap (disebut titik didih). Cairan yang memiliki tekanan uap yang lebih tinggi pada suhu kamar memiliki titik didih yang lebih rendah daripada cairan yang memiliki tekanan uap lebih rendah. Jika uap diatas cairan terkumpul dan didinginkan, uap akan terembunkan dan komposisinya sama dengan komposisi senyawa yang terdapat pada uap yaitu senyawa yang mempunyai titik didih lebih rendah. Penetapan kadar air dengan metode azeotroph biasanya digunakan untuk bahan makanan yang banyak mengandung air seperti rempah-rempah. Ketika campuran azeotroph didihkan, fase uap yang dihasilkan memiliki komposisi yang sama dengan fase cairnya.
Prosedur pertama pada penetapan kadar air yaitu penjenuhan toluen. Toluen merupakan sejenis pelarut cair yang membias tanpa warna dengan bau khas dengan titik didih 111 C. Toluen harus dijenuhkan karena struktur toluen dapat mengikat sedikit air (terdapat rongga untuk mengikat air), sehingga jika toluen masih bersifat anhidrat, jika demikian maka akan menghasilkan kadar air yang tidak sesuai (palsu). Penjenuhan dilakukan dengan mencampurkan aquades dengan toluen lalu dikocok kuat, didiamkan hingga terpisah dan diambil lapisan toluen. Pengocokan kuat ini berfungsi melepasakan ikatan air yang terperangkap dalam toluen sehingga air tersebut terikat pada bagian air yang ditambahkan dengan prinsip like dissolve like (air merupakan pelarut polar sedangkan toluen pelarut non polar).
Prosedur kedua yaitu penentuan kadar air, dilakukan dengan menghaluskan simplisia. Hal ini dilakukan untuk memperbesar luas permukaan sehingga sel-sel pada bahan lebih mudah untuk kontak dengan pelarutnya, dan zat aktif dalam simplisia akan lebih mudah tertarik keluar. Setelah itu, simplisia yang telah halus dimasukkan ke dalam labu alas bulat dan ditambahkan toluen yang telah jenuh. Adapun alasan penggunaan toluen dalam penetapan kadar air dengan metode destilasi karena titik didih toluen mendekati titik didih air (titik didih toluen 111 C dan titik didih air 100 C), selain itu karena berat jenis toluen yang berbeda dengan air (berat jenis toluen adalah 0,86 dan berat jenis air 0,989), toluen juga mampu menarik air namun tidak bercampur dengan air. Selanjutnya alat destilasi dipasang dan dilakukan destilasi. Uap hasil destilasi diembunkan dengan bantuan kondensor dan melewati pipa kondensor dengan tekanan rendah, apabila uap melewati tekanan atau suhu rendah maka uap mengembun dan jatuh pada tabung penampung. Pada proses destilasi, pemanasan bertujuan untuk mempercepat proses penguapan air dan toluen. Penambahan batu didih ke dalam labu alas bulat sebelum dilakukan destilasi berfungsi meratakan panas disetiap bagian bahan yang dipanaskan dan untuk menghindari terjadinya letupan akibat perbedaan titik didih di beberapa bagian bahan dalam labu alas bulat. Hasil destilasi berupa campuran air dan toluen yang ditampung dalam corong pisah dan didiamkan hingga terpisah lalu dipisahkan air dari lapisan toluen. Fase air akan berada dibawah dan fase toluen berada diatas, hal ini dikarenakan berat jenis air yang lebih besar dibanding berat jenis toluen. Air yang telah disisihkan diukur dengan labu ukur, lalu dihitung kadar air simplisia.
Alat destilasi terdiri dari beberapa bagian. Labu alas bulat sebagai wadah menyimpan sampel yang akan didestilasi. Kondensor atau pendingin berfungsi untuk mendinginkan uap destilasi yang melewati kondensor sehingga terjadi pengembunan. Termometer untuk mengamati suhu. Corong pisah untuk menampung destilat. Pipa penghubung berfungsi menghubungkan antara kondensor dengan wadah penampung destilat, dan pemanas berfungsi untuk memanaskan sampel yang tedapat dalam labu alas bulat.
Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh kadar air pada simplisia daun mahkota dewa (Phaleria macrocarpa folium) adalah 9,59 %, kulit buah jeruk keprok (Citrus nobilis fructus) adalah 3,99 % dan buah mengkudu (Morinda citrifolia fructus) adalah 0,99 %. Hal ini menunjukkan bahwa simplisia daun mahkota dewa, buah mengkudu, dan kulit buah jeruk keprok memiliki kadar air yang masih dalam rentang ketentuan dan memenuhi syarat kriteria karena tidak melewati batas kadar air yang ditetapkan yaitu kurang dari 10 % dengan batasan minimal sebesar 1 %. Apabila simplisa memiliki kadar air yang lebih dari 10 % maka dikhawatirkan mudah ditumbuhi mikroba dan terjadi reaksi enzimatik terutama dengan kandungan senyawa metabolit sekunder pada simplisia sehingga dapat menurunkan kualitas dari simplisia tersebut.
Adapun faktor yang mempengaruhi kadar air dari suatu simplisia adalah jenis simplisia yang berbeda, tempat penanaman yang berbeda (faktor tanah dan lingkungan, dan cuaca), lamanya proses pengeringan simplisia, dan tempat penyimpanan simplisia (kelembaban dan suhu ruangan).
Keuntungan dari metode destilasi azeoptroph adalah kadar air dapat ditetapkan langsung dari hasil akhir merupakan nilai kadar air yang nyata bukan karena kehilangan berat contoh, waktu analisis lebih singkat, peralatan sederhana, mudah ditangani dan dapat menghindari pengaruh kelembaban serta dapat mencegah oksidasi selama pemanasan.
Kekurangan dari metode destilasi azeotroph adalah permukaan alat gelas harus selalu bersih dan kering, senyawa alkohol atau gliserol mengkin terdestilasi bersama air dan dapat menyebabkan data yang diperoleh lebih tinggi daripada data sebenarnya, pelarut yang digunakan mudah terbakar dan ketelitian membaca volume air yang terkondensasi terbatas sehingga akan berpengaruh pada nilai keakuratan dari kadar air yang akan ditentukan dari suatu simplisia yang diteliti.
Manfaat pengujian ini dalam bidang farmasi adalah untuk mengetahui nilai kadar air yang terdapat dalam suatu simplisia tanaman yang berpotensi sebagai obat sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku yang baik, aman serta stabil sehingga dapat diformulasikan dalam sediaan - sediaan farmasi. Manfaat lain dari pengujian ini dalam bidang farmasi adalah untuk menjamin kualitas dari simplisia agar simplisia dapat aman dari pengaruh kadar air yang berlebih selama proses ekstraksi hingga pada proses penyimpanannya, dimana kadar air yang berlebih dari suatu simplisia sangat rentang ditumbuhi oleh mikroba atau mikroorganisme lain yang dapat merusak kualitas dari simplisia yang dibuat.
G. Kesimpulan
Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Kadar air sampel simplisia daun mahkota dewa (Phaleria macrocarpa folium) adalah 9,59 %.
2. Kadar air sampel simplisia buah mengkudu (Morinda citrifolia fructus) adalah 0,99 %.
3. Kadar air sampel simplisia kulit buah jeruk keprok (Citrus nobilis fructus) adalah 3,99 %.
DAFTAR PUSTAKABambang, Setiawan. 2012. Efek Jus Daun Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa) sebagai Antimodifikasi Protein Plasma Akibat Reaksi Glukosilasi. Jurnal Kimia Farmasi Vol 2 No.1.Djauhariya, Enda. 2003. Mengkudu (Morinda citrifolia) Tanaman Obat Potensial. Pengembangan Teknologi TRO Vol 15 No 1.Firman, N. 2005. Mahkota Dewa dan Manfaatnya. Ganeca: Jakarta.Guanther, Ernest. 1989. Minyak Atsiri Jilid 1 Cetakan 1. Universitas Indonesia Press: Jakarta.
Oxtoby, Gils. 2001. Prinsip Kimia Modern. EGC: Erlangga.
Santi, L.A, dkk. 2012. Komposisi Kimia dan Profil Polisakarida Rumput Laut Hiko. Jurnal Alavastika Vol 3 No. 2.
Sudarmadji, Slamet. 2010. Analisis Bahan Makanan dan Pertanian. Liberty: Yogyakarta.Suharmiati. 2003. Khasiat dan Manfaat Jati Belanda, si Pelangsing dan Peluruh Kolesterol. Agromedia: Jakarta.
Svehla. 1979. Buku Ajar Vogel: Analisis Anorganik Kualitatif dan Kuantitatif Mikro dan Semimikro. PT Media Pustaka: Jakarta.Suprapti, Kes. 2003. Aneka Olahan Mengkudu. PT Kanisius: Yogyakarta.Syamsuri, Haji. 2006. Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasetika. EGC: Jakarta.Winarto, F.G. 2004. Kimia Pangan dan Gizi. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.